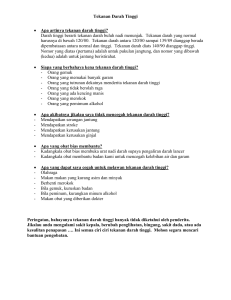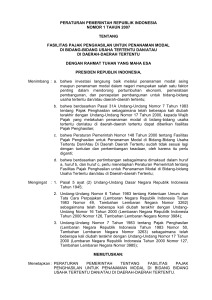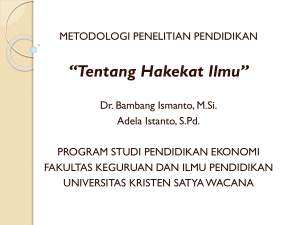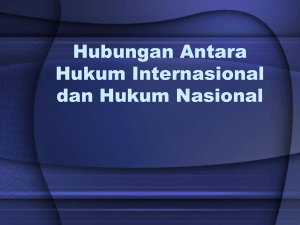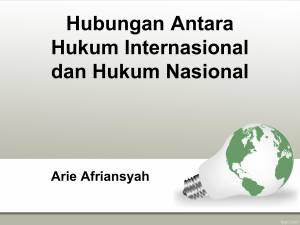membongkar monisme dan membangun pluralisme epistemologis
advertisement

MEMBONGKAR MONISME DAN MEMBANGUN PLURALISME EPISTEMOLOGIS: TANTANGAN SOSIOLOGI DI ERA GLOBALISASI Oleh: Nasikun I 1. Di hadapan kenyataan bahwa sosiologi lahir dua kali dari rahim dua tradisi keilmuan atau epistemologi yang berbeda, yakni epistemologi “positivistisnaturalistis” yang dipinjam dari ilmu-ilmu alam dan epistemologi “historiskulturalistis” atau “hermeneutis” dari ilmu humaniora (baca: a.l., Marcelo Truzi, 1974 dan Henry Etzkowitz dan Ronald M. Glassman, 1991), adalah sangat menarik menyaksikan betapa perkembangan sosiologi di Indonesia sampai saat ini ternyata masih terlalu kuat dikuasai oleh dominasi penggunaan monisme tradisi keilmuan atau epistemologi positivistis-naturalistis. Kita memang tidak dapat mengingkari bahwa di dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan munculnya “eksplosi” kecenderungan baru di kalangan sementara ahli sosiologi di Indonesia untuk melakukan kajian tentang berbagai fenomena sosial di atas landasan epistemologi historis-kulturalistis atau hermeneutis, akan tetapi kecenderungan baru itu sejauh ini masih belum mencapai skala dan “magnitute” yang cukup kuat untuk menggoyahkan dominasi penggunaan monisme epistemologis dan metodologis positivistis-naturalistis di kalangan para ahli sosiologi di Indonesia selama ini. 2. Kita semua mengetahui bahwa kontroversi tentang apakah ilmu-ilmu sosial, tidak terkecuali sosiologi, harus dikembangkan mengikuti tradisi keilmuan positivistisnaturalistis atau historis-kulturalistis memang bukan merupakan suatu fenomena yang baru. Gugatan klasik dari kaum subyektivis yang menolak pendekatan positivistis-naturalistis di dalam ilmu-ilmu sosial bahkan sudah dilakukan jauh-----------------------------------------*). Disampaikan sebagai bahan diskusi pada Seminar Nasional Strategi Peningkatan Daya Saing Ilmu-Ilmu Sosial di Era Global, yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja tanggal 12 November 2005. jauh hari oleh ahli filsafat neo-idealis Jerman dari akhir abad 18 bernama William Dilthey terhadap pemikiran metafisika Auguste Comte, dan terutama terhadap argumen John Stuart Mill yang dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa: “Jikalau kita ingin keluar dari kegagalan ilmu-ilmu sosial dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam, maka satu-satunya harapan kita haruslah digantungkan pada penggunaan di dalam ilmu-ilmu sosial metode-metode yang telah terbukti sangat berhasil mendorong perkembangan ilmu-ilmu alam” (Truzi, 1974). Melalui gugatannya itu Dilthey sesungguhnya sedang berusaha untuk meyakinkan para penganut tradisi intelektual positivistis-naturalistis di dalam ilmu-ilmu sosial akan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara ilmu-ilmu sosial dan ilmuilmu alam, dan yang oleh karena itu mengharuskan ilmu-ilmu sosial untuk meninggalkan penggunaan metodologi yang digunakan oleh ilmu-ilmu alam dan sebaliknya membangun dan mengembangkan basis metodologinya sendiri. 1 Jikalau oleh karena karakter obyektif dari “obyek” kajiannya ilmu-ilmu alam bergumul untuk menemukan “hukum-hukum” yang bekerja di belakang dunia alam fisik, maka oleh karena karakter dunia sosial yang tidak hanya memiliki dimensi obyektif akan tetapi juga dimensinya yang bersifat subyektif maka pergumulan ilmu-ilmu sosial harus terutama ditujukan untuk menemukan ultimate understanding melalui pengembangan “insights” tentang dunia sosial yang menjadi “subyek” pengamatan dan kajian mereka, yang di dalam ilmu-ilmu alam biasa disebut sebagai “obyek” pengamatan. 3. Pertanyaannya adalah ini: mengapa, sesudah melalui kurun waktu yang sangat panjang, perkembangan sosiologi sejawat ilmu-ilmu sosial pada umumnya “panggah” atau tetap saja terjadi di bawah hegemoni monisme penggunaan epistemologi, teori, dan metodologi positivistis-naturalistis? Menurut Stephen Jay Kline (1995) di dalam bukunya berjudul Conceptual Foundations for Multidisciplinary Thinking, jawabnya harus ditemukan di dalam keunggulan ilmu-ilmu alam (baca: natural sciences) dan aplikasi metode-metode keilmuan ilmu-ilmu tersebut oleh ilmu-ilmu sosial di dalam mengembangkan suatu sistem intelektual yang dapat memberikan kepada umat manusia kemampuan luar biasa untuk memahami hukum-hukum alam tempat kehidupan mereka bergantung. Bukti empiris paling nyata dari keberhasilan itu dengan mudah dapat ditunjukkan melalui keberhasilan ilmu-ilmu alam dalam mentransformasikan sistem ekonomi dunia dari karakternya sebagai apa yang oleh Karl Polanyi disebut sebagai sistem ekonomi yang “luluh” (embedded economy) menuju karakternya sebagai suatu sistem ekonomi yang “terurai” atau terdiferensiasi (differentiated economy) dan yang oleh karenanya memiliki kemampuan untuk menciptakan kemakmuran material yang luar biasa meski sejauh ini ia harus dicapai dengan biaya sosial dan lingkungan yang sangat besar. 4. Keunggulan sistem intelektual tersebut pada gilirannya memiliki sumbernya di dalam bekerjanya dua hal berikut. Yang pertama kita temukan di dalam bekerjanya apa yang secara sangat longgar dapat disebut sebagai “metode-metode ilmiah” (scientific methods), sementara sumbernya yang kedua dapat kita jumpai di dalam berkembangnya spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan yang secara progresif semakin lama menjadi sangat luas. Pada tahapan awal perkembangannya, metode-metode keilmuan dan spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan itu memang tidak menimbulkan masalah yang berarti. Akan tetapi, sebagaimana yang akan disampaikan pada penyajian pokok bahasan yang lain, ketika spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan berkembang terlalu jauh, maka sistem intelektual tersebut menjadi semakin kehilangan kemampuan esensialnya untuk melihat dan menjelaskan hal-hal berikut: (1) deskripsi tentang keseluruhan kerangka kerja ilmu pengetahuan yang menempatkan beragam disiplin ilmu pengetahuan di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain; (2) deliniasi tentang apa yang dapat direpresentasikan oleh setiap disiplin ilmu pengetahuan; (3) perkembangan pemahaman (insights) tentang kesamaankesamaan dan perbedaan-perbedaan diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan di dalam kaitannya dengan kompleksitas sistem paradigmatis, variasi-variasi 2 perilaku dan prinsip-prinsip keilmuan di dalam kurun waktu yang berbeda dan jenis-jenis konsep yang mereka analisa; dan (4) bagaimana berbagai disiplin ilmu pengetahuan berhubungan sangat erat satu dengan yang lain ketika mereka diterapkan untuk mengungkapkan masalah-masalah tertentu; bagaimana ilmuwan dapat menilai kemungkinan-kemungkinan bahwa bidang-bidang kajian yang mereka lakukan dibangun di atas pertanyaan-pertanyaan yang sesat, dan bahwa penelitian-penelitian mereka dilakukan di atas pilihan penggunaan pendekatanpendekatan keilmuan yang keliru dan oleh karena itu telah menghasilkan kesalahan-kesalahan pemahaman yang sangat mendasar; dan bagaimana keduanya sangat esensial bagi pengembangan kesyahihan metodologi masingmasing disiplin ilmu pengetahuan dan keseluruhan sistem intelektual. 5. Semua itu mengimplikasikan pentingnya, jikalau bukan keharusan pengembangan pendekatan interdisipliner dan/atau transdisipliner untuk memberikan kemampuan ilmu pengetahuan dalam empat hal yang dimaksudkan oleh Kline di atas. Perkembangan ilmu pengetahuan dengan demikian tidak boleh hanya dipahami melalui “koroborasi” statistik atau “falsifikasi” hipotesis-hipotesis. Pandangan keilmuan yang demikian, seperti yang dikemukakan oleh Neurath (dalam Martinez-Alier, 1995), sangat tegas menolak penggunaan monisme epistemologis, teoritis dan metodologis, dan sebaliknya menganjurkan pentingnya penerimaan pluralisme epistemologis, teoritis dan metodologis sebagai basis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mengikuti logika yang sama, Martinez-Alier (1995: 136) mengusulkan pentingnya apa yang ia sebut sebagai “orkestrasi ilmu pengetahuan” (orchestration of sciences). Seperti halnya dengan Neurath, yang berpendapat bahwa pemahaman tentang sejarah penemuan-penemuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan tidak boleh terjebak ke dalam “reduksionisme” dan “piramidisme” Auguste Comte, Martinez-Alier memiliki keyakinan yang kuat bahwa untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih jernih tentang isu-isu “pembangunan manusia yang berkelanjutan” (sustainable human development) diperlukan pendekatan multidisipliner dan/atau transdisipliner. 6. Sebagai konsekuensi dari penerimaan dan penggunaan pendekatan yang demikian, dunia ilmu pengetahuan kontemporer paling sedikit akan menuai beragam keuntungan-keuntungan berikut. Pertama, pengembangan pendekatan multidispliner atau transdisipliner akan memberikan kepada para ilmuwan pemahaman yang lebih jernih tentang bagaimana beragam minat dan disiplin keilmuan berkaitan tali-temali dengan keseluruhan sistem intelektual dan dengan dunia alam fisik dan sosial yang menjadi obyek dan/atau subyek kajian mereka. Kedua, pada saat yang sama, para peneliti (tidak terkecuali para ahli sosiologi dan peneliti ilmu-ilmu sosial pada umumnya) akan semakin memahami pula bahwa penilaian-penilaian lebih komprehensif yang mereka peroleh dari pengembangan program-program multidispliner atau transdisipliner akan membantu mereka di dalam memperoleh pemahaman yang lebih “penuh” dan lebih “otentik” tentang disiplin ilmu pengetahuan masing-masing. Di dalam konteks pengembangan program-program studi ilmu-ilmu sosial, tidak terkecuali program studi sosiologi, pengembangan perspektif multidisipliner atau transdisipliner akan memberikan 3 keuntungan bagi para ilmuwan dan peneliti ilmu-ilmu sosial untuk lebih memahami tali-temali bekerjanya berbagai kekuatan sosial (baik yang berkarakter obyektif maupun subyektif, dan pada tataran makro maupun mikro) di belakang berbagai realitas sosial dan kultural sebagai akomodasi dan aplikasi berbagai teori ilmu-ilmu sosial beserta implikasi-implikasi dari metode-metode penelitian yang diturunkan dari pilihan teori-teori tersebut. 7. Apa implikasi kelembagaan dari semua itu bagi perumusan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan? Menurut hemat saya aktualisasinya paling sedikit akan mengungkapkan dirinya di dalam tiga dataran kebijakan berikut. Pada dataran yang pertama, ia harus mengungkapkan dirinya dalam bentuk kebijakan pengembangan kurikulum yang dibangun di atas akomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, di mana komposisi mata kuliah untuk tiap program studi memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan dialog antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan disiplin ilmu pengetahuannya sendiri. Pada dataran kebijakan yang kedua, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan program studi ilmu-ilmu sosial, kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme epistemologis, teoritis, dan metodologis yang selama ini sangat menguasai bukan hanya penyelenggaraan program studi sosiologi akan tetapi bahkan nyaris semua program studi ilmu sosial di Indonesia. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah suatu kebijakan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang membuka pintu lebar-lebar bagi pengembangan beragam tradisi keilmuan atau epistemologi beserta dengan konsekuensi-konsekuensi pilihan perspektif teoritis dan metodologi penelitian yang menjadi turunan masing-masing. Kebijakan yang ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya, menyangkut bagaimana struktur organisasi lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan harus dikembangkan. Salah satu diantara beragam wujud pengungkapannya adalah kebijakan untuk mengelompokkan berbagai program studi ke dalam jumlah kelompok program studi yang lebih kecil, yang pada tingkat program studi S2 dan S3 dapat diungkapkan ke dalam pengembangan tiga atau empat “Graduate School”, di mana “Graduate School of Social Science and Humanity” merupakan salah satu diantaranya. Tentu saja harus dipahami bahwa semua kebijakan itu jelas tidak akan mampu mencapai tujuannya dengan baik, kecuali jikalau pada saat yang sama terjadi transformasi di dalam kualitas seluruh sumber daya dan mutu “governance” atau tata kepemerintahan lembaga pendidikan yang mendukungnya. 8. Hanya dengan semua itu, maka para ahli dan peneliti ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi, akan memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi dan terpercaya untuk mengikuti persaingan profesional yang akan makin keras di era globalisasi gelombang ketiga di masa depan. Hanya dengan semua itu maka para ahli dan peneliti ilmu-ilmu sosial akan memiliki kemampuan untuk memahami kenyataan dunia yang ada di hadapan mereka dengan lebih jernih dan benar melampaui pemahaman manusia-manusia gua di dalam metafora “gua Plato” (Garon, 2003: 25), yang mengira bahwa bayang-bayang mereka di dinding gua di hadapan 4 mereka merupakan kenyataan dunia mereka yang sesungguhnya. Lebih dari semua itu, hanya dengan semua itu maka para ahli dan peneliti ilmu-ilmu sosial di negeri ini akan memiliki pemahaman kritis yang lebih jernih dan benar melampaui pemahaman arus besar pemahaman para ahli tentang dinamika proses globalisasi yang tengah kita hadapi saat ini dan implikasi isu-isu sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkannya. II 9. Dengan semua itu kini saya ingin mengajak para peserta pertemuan ini untuk memahami dengan lebih seksama tentang tantangan perubahan-perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini, dan yang membedakannya dari pemahaman arus besar para ahli globalisasi yang melalui perspektif mereka yang melihat realita globalisasi dan isu-isu sosial dan kemanusiaan yang sejauh ini ditimbulkannya bukan hanya sebagai realita yang sesungguhnya tanpa menyadari bahwa realita tersebut sesungguhnya hanya merupakan bayang-bayang dari kepentingan kekuatan-kekuatan global yang tidak “legitimate”. Dengan semua itu saya juga ingin mengajak para peserta seminar ini untuk memahami bahwa dinamika proses globalisasi yang tengah kita hadapi saat ini, yang oleh Robbie Robertson (2003) disebut sebagai globalisasi gelombang ketiga (dan yang kini lebih dikenal sebagai globalisasi neo-liberal), memiliki karakter dan dinamika yang sangat berbeda dari karakter dan dinamika globalisasi gelombang pertama dan kedua. Kedua, pada saat yang sama, kita perlu melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang implikasi dari ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi negara-negara di Dunia Ketiga, terutama implikasinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan universitas di negara-negara tersebut. 10. Sebagaimana kita ketahui, logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari idelologi neo-liberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrim. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas (Kymlycka, 1999: 95), neo-liberalisme percaya pada pentingnya institusi pemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasikorporasi tansnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas, sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan individu (Gelinas, op. cit., 2003: 24). 11. Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai Unholy Trinity (baca: IMF, Bank Dunia, dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang memiliki nilai tidak dapat dipertahankan dari komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global: tidak juga air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara- 5 negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut (Gelinas, ibid: 31): (1) Deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods, yang terjadi sejak tahun 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif. (2) Deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematik dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (structural adjustment) di bawah pengawalan IMF dan Bank Dunia untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global. (3) Deregulasi stock markets yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua stock markets di seluruh dunia. (4) Deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi pelayanan-pelayanan yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional. (5) Proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (tax and banking havens) sejak pertengahan tahun 1990-an, yang telah menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik. 12. Semua itu telah menyebabkan globalisasi gelombang ketiga atau globalisasi neoliberal secara mendasar memiliki dinamika dan implikasi yang sangat berbeda dari dinamika dan implikasi globalisasi gelombang pertama dan kedua. Jikalau di era globalisasi gelombang pertama dan kedua ekstraksi kekayaan negara-negara sedang berkembang di Dunia Ketiga dilakukan dengan menggunakan mekanisme “akumulasi primitif” melalui beragam bentuk kekerasan fisik yang terbuka seperti penaklukan dan kolonisasi, perampokan dan perbudakan, serta ekslpoitasi pertanian dan perdagangan antar benua, maka di era globalisasi gelombang ketiga ekstraksi kekayaan negara-negara Dunia Ketiga dilakukan dengan cara-cara yang sangat lembut dan tersembunyi melalui regulasi sistem perdagangan internasional yang di atas permukaan tampak sangat bebas dan demokratis akan tetapi yang di bawah permukaan sesungguhnya seringkali jauh lebih eksploitatif dan tidak adil. Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau keberhasilan globalisasi gelombang ketiga yang telah membawa perkembangan peradaban umat manusia ke tingkat yang selama ini tidak pernah terbayangkan, harus berjalan seiring dengan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan di banyak negara sedang berkembang. Gelinas (ibid: 165-166) menyebut beberapa tragedi kemanusiaan berikut diantara yang paling penting: (1) 4 sampai 6 milyar penduduk dunia berada di 127 negara terbelakang berada di dalam kondisi kemiskinan yang berat; (2) 49 negara paling terbelakang secara teknologis mengalami kebangkrutan; (3) pendapatan per kapita per tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalani penurunan dari keadaan 10, 15, 20 dan bahkan 30 tahun yang lalu; 6 (4) 2,8 milyar penduduk di negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS (Amerika Serikat) per hari; (5) 1,3 milyar penduduk di negara-negara yang sama bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS; (6) 2,6 milyar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai; dan (7) 1,4 penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih. 13. Laporan statistik UN Human Development Report tahun 1996 (Tehranian, op. cit., 1999: 157) menguatkan semua itu dengan menunjukkan semakin menguatnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi dunia melalui penyajian statistik berikut: 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima lebih dari 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen penduduk paling miskin hanya menerima 1,4 persen. Mengutip laporan Rummel tahun 1994, Tehranian menyebutkan pula bahwa sepanjang kurun waktu antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1990 telah terjadi sekitar 250 perang antar negara dan perang sipil di berbagai negara yang merenggut kematian lebih dari 100 juta tentara dan 100 juta penduduk sipil. Lebih dari itu, jikalau pada abad 18 dan abad 19 kematian prajurit yang terjadi dalam peperanngan hanya mencapai angka 50 dan 60 orang per 1 juta penduduk dunia, angka itu meningkat secara sangat dramatik pada abad 20 menjadi 460 kematian per 1 juta penduduk dunia. 14. Kenyataan-kenyataan itu pula yang antara lain telah menjadi alasan Tehranian (1999: 156) untuk menyebut abad 20 sebagai “abad kematian yang direncanakan” (a century of death by design). Memasuki akhir abad 20 sejumlah cendekiawan terkemuka di dunia bahkan telah menengarai terjadinya “kematian” banyak hal yang selama ini menjadi fondasi dari tata kehidupan dunia (Tehranian, op. cit., 1996): mulai dari “the end of ideology” (Bell, 1960), “the end of history” (Fukuyama, 1989), “the end of modernity” (Mowlana dan Wilson, 1990), “the end of journalism” (Katz, 1992), “the end of geography” (Mosco, 1994), “the end of racism” (D’Souza, 1995), dan “the end of work” (Rifkin, 1995), sampai dengan “the end of university” (Tehranian, 1996). 15. Di dalam kaitannya dengan isu yang terakhir tentang “kematian universitas”, yang sangat relevan bagi penyajian tema pembicaraan kita kali ini, globalisasi telah membuat universitas di mana-mana di seluruh dunia, dan berbagai ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan, semakin kehilangan otonominya sebagai suatu “culture-conserving”, “culture-creating” dan “civilizing institituion” di dalam mewujudkan peran dan fungsinya untuk membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penindasasan, ketidakadilan dan dehumanisasi, dan sebaliknya untuk mewujudkan misi “liberasi” (liberation) dan “pencerahan” (enlightnment) bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana yang akan disampaikan lebih jauh pada halaman-halaman berikut, di bawah tekanan globalisasi teknologi informasi genre baru, yang menjadi salah satu elemennya yang paling penting, di mana-mana di seluruh permukaan bumi 7 universitas semakin kehilangan otonomi dan kemampuan mereka untuk mewujudkan hampir semua peran dan fungsi tradisionalnya yang sangat esensial untuk melakukan produksi, preservasi, dan transmisi pengetahuan (Noam, 1995), dan pendidikan moral, sosialisasi keilmuan, kritik sosial, serta sertifikasi profesional dan rekruitmen elit (Tehranian, 1996). Melalui kehadiran revolusi teknologi informasi yang telah menciptakan perubahan-perubahan sangat mendasar di dalam struktur organisasi dan mekanisma kerja universitas sejak tahun 1980-an, globalisasi gelombang ketiga bahkan telah menciptakan berbagai paradoks perkembangan universitas yang selama ini belum pernah terjadi. 16. Sebagaimana dikemukakan oleh Noam dan Tehranian, di bawah dukungan revolusi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, globalisasi telah berhasil mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 4 sampai 6 persen tiap tahun, yang berarti telah menghasilkan kelipatan pertumbuhan dua kali hanya dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Seperti yang terjadi dalam bidang-bidang yang lain, spesialisasi merupakan mekanisme yang bekerja di belakang perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu. Salah satu sebabnya yang sangat penting bersumber dalam keterbatasan kemampuan finansial dan sumber daya fisik yang dimiliki oleh universitas, sehingga aktualisasi kemampuan para ilmuwan untuk menguasai pengetahuan yang semakin banyak mengenai bidang-bidang yang semakin sempit terpaksa harus menemukan solusinya dalam pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti lembaga-lembaga “thinktanks”, konsultansi, korporasi riset dan pengembangan yang dimiliki oleh berbagai departemen dan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan nonpemerintah. 17. Sebagaimana sudah disebutkan di muka, spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan memang merupakan salah satu kekuatan sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan berkembang terlalu jauh, apalagi ketika dorongan yang menggerakkannya dikendalikan oleh kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka sistem intelektual yang menjadi tempatnya berpijak akan semakin kehilangan kemampuan esensialnya untuk melihat dan menjelaskan hal-hal berikut: (1) deskripsi tentang keseluruhan kerangka kerja ilmu pengetahuan yang menempatkan beragam disiplin ilmu pengetahuan di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain; (2) deliniasi tentang apa yang dapat direpresentasikan oleh setiap disiplin ilmu pengetahuan; (3) perkembangan pemahaman (insights) tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan kompleksitas sistem paradigmatik yang mendasarinya; dan (4) bagaimana berbagai disiplin ilmu pengetahuan berhubungan sangat erat satu sama lain ketika mereka diterapkan untuk mengungkapkan masalah-masalah tertentu. Yang terakhir memiliki kaitan yang erat dengan isu tentang bagaimana ilmuwan dapat menilai kemungkinan-kemungkinan bahwa bidang-bidang kajian yang mereka lakukan dibangun di atas pertanyaan-pertanyaan yang sesat, dan bahwa penelitian-peneilitian mereka dilakukan di atas pilihan penggunaan 8 pendekatan-pendekatan keilmuan yang keliru dan oleh karena itu telah menghasilkan kesalahan-kesalahan pemahaman yang sangat mendasar; dan bagaimana keduanya sangat esensial bagi pengembangan kesyahihan metodologi masing-masing disiplin ilmu pengetahuan dan keseluruhan sistem intelektual yang mendasarinya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Stephen Jay Kline (1995) akan dapat terjadi atas perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi globalisasi saat ini di masa yang akan datang. 18. Sebagai akibatnya, fungsi pertama universitas untuk mengembangkan (ilmu) pengetahuan semakin banyak diambilalih oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta yang memiliki dukungan dana yang kuat dan menuntut keahlian yang semakin terspesialisasi. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini secara internal dapat dilakukan universitas melalui kebijakan-kebijakan pengembangan infrastruktur dan iklim akademik, berkat dukungan perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi modern, kini harus dilakukan melalui persaingan yang semakin tidak menguntungkan dengan lembaga-lembaga dan jaringan-jaringan pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin banyak berkembang di luar universitas dengan dukungan infrastruktur yang jauh lebih baik dan dana yang lebih besar. 19. Dampak lebih jauh dari semua perkembangan itu adalah bahwa peran universitas untuk mengintegrasikan perkembangan unit-unit pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya menjadi semakin problematik. Tanpa kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar, program-program dan pusat-pusat studi yang menjadi ujung tombak universitas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan semakin sulit dikendalikan untuk berkembang menjadi “kerajaan-kerajaan” kecil yang memiliki hubungan yang minimal diantara satu dengan yang lain. Di hadapan tawaran dukungan sumber dana yang besar dari luar, tidak jarang bahkan dari lembaga-lemaga dana yang memiliki kaitan dengan kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka program-program dan pusat-pusat studi yang dimiliki universitas akan berkembang mengikuti irama dan dinamika mereka sendiri-sendiri. Sebagai akibatnya, berbagai disiplin ilmu pengetahuan menjadi semakin tidak dapat berbicara satu sama lain. Disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam, misalnya, yang pada abad limabelas dan enambelas memiliki kebesaran dan superiotas yang sangat tinggi oleh karena para ahlinya pada umumnya memiliki kapasitas sebagai ahli-ahli filsafat yang tidak hanya memiliki penguasaan atas fakta-fakta empiris akan tetapi juga konsep-konsep kemanusiaan yang kuat (Heidegger, 1977), kini semakin tidak dapat berbicara dengan para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Banyak diantara mereka menganggap para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora lebih banyak membangun argumen keilmuan mereka di atas opini dan akal sehat yang tidak memiliki dukungan fakta-fakta empiris yang kuat dan terpercaya. Sebaliknya, disiplin ilmu-ilmu sosial yang pada awal kelahirannya berkembang dengan meminjam epistemologi positivistis-naturlistis dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam (Etzkowitz, 1991), kini semakin bersikap skeptis terhadap kesyahihan fakta-fakta empiris yang “keras” yang dihasilkan melalui penggunaan metode-metode penelitian positivistis-naturalistis, dan oleh karena 9 itu juga menjadi semakin tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan sejawat-sejawat mereka dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam. Mereka menganggap banyak ahli ilmu-ilmu pengetahuan alam memberikan kepercayaan terlalu tinggi pada fakta-fakta empiris yang “keras”, sebaliknya kurang menaruh perhatian pada pentingnya refleksi dan kontemplasi. 20. Semua itu telah menyebabkan fungsi liberasi universitas dan ilmu pengetahuan untuk membantu masyarakat dan umat manusia melepaskan diri dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan dan dehumanisasi juga menjadi semakin problematik. Meminjam argumen Schiller (Webster, 1995), di tengah era globalisasi teknologi informasi, di mana-mana di seluruh dunia, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, universitas semakin tidak memiliki kemampuan untuk mencegah hadirnya paling sedikit tiga ragam perubahan sangat problematik berikut. Pertama, sebagai implikasi dari perkembangan dan aplikasi teknologi informasi dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, kini universitas harus menyaksikan hadirnya dinamika perkembangan masyarakat yang semakin dikendalikan oleh “kriteria-kriteria pasar”. Inovasi-inovasi informasi dan komunikasi baru dan semua produk inovasi lain yang semula diharapkan akan dapat menjadi kekuatan pendorong sangat penting bagi dinamika perkembangan masyarakat di masa mendatang, ternyata telah berkembang semakin dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan pasar di dalam proses pembelian, penjualan, dan perdagangan untuk alasan keuntungan. Sentralitas prinsip-prinsip pasar di dalam ketiga kegiatan itu pada gilirannya telah menghasilkan terjadinya “komodifikasi” dan “komersialisasi” informasi, dan dengan demikian hanya akan menjamin ketersediaan informasi sejauh ia menghasilkan keuntungan; dan bagi para pengguna informasi, hanya akan dapat diperoleh sejauh mereka dapat dan mampu membelinya. 21. Kedua, globalisasi teknologi informasi juga telah dan akan mengakibatkan masyarakat dan ekonomi kita semakin tumbuh menjadi sebuah “corporate capitalism” yang akan semakin didominasi oleh institusi-institusi korporatis di dalam bentuk organisasi-organsisasi oligopolistis atau bahkan monopolistis. Ketiga, sebagai hasil dari keduanya, yang telah dan akan kita saksikan semakin transparan di hadapan mata publik adalah meningkatnya kesenjangan kelas (class inequality) yang akan semakin menguasai dinamika perkembangan masyarakat dan ekonomi kita di masa mendatang. Kelas, misalnya, akan semakin menentukan siapa yang akan memperoleh jenis informasi macam apa dan dalam jumlah seberapa banyak, serta semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Di dalam situasi seperti itu, hanya mereka yang berada pada lapisan atas di dalam struktur sosial masyarakat kita yang akan memperoleh keuntungan yang berarti dari perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks pemanfaatannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hal itu juga berarti bahwa hanya mereka yang berada pada lapisan atas di dalam struktur sosial masyarakat kita yang akan memperoleh keuntungan yang berarti dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 22. Yang menjadi tantangan kita saat ini dan di masa depan adalah bagaimana di bawah tekanan globalisasi gelombang ketiga yang semakin meraja, peran 10 universitas dan ilmu pengetahuan bagi liberasi umat manusia dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, dan dehumanisasi harus dikontekstualisasi dan direvitalisasi. Di dalam ungkapan lain, tantangan sangat besar yang harus dapat dijawab oleh setiap universitas di masa depan adalah bagaimana misinya itu harus dirumuskan dan didefinisikan kembali ke dalam bentuknya yang lebih kontekstual untuk menghadapi tekanan perubahan-perubahan global yang semakin keras saat ini dan di masa depan. Bagaimana, misalnya, misi universitas harus dikontekstualisasi dan direvitalisasi sehingga aktualisasinya melalui pelaksanaan program-program tridharma universitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat benar-benar memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan perubahan-perubahan global. Tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan tentang bagaimana misi itu harus didefinisikan kembali dan direvitalisasi ke dalam perumusan kebijakankebijakan organisasional atau institusional universitas. 23. Di dalam konteks semua itulah uraian tentang implikasi kelembagaan dari semua itu bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah disampaikan pada butir 7 di muka harus kita pahami dan kita tempatkan. Untuk mengukuhkan semua itu, sekaligus untuk menutup penyajian ini, sebuah kebijakan pengembangan kelembagaan universitas yang secara khusus dirancang untuk mengemban tiga fungsi berikut perlu dikembangkan. Meminjam ungkapan Daly dan Cobb, Jr. (1998), fungsi pertama yang harus menjadi pusat perhatian program kelembagaan universitas tersebut menyangkut kajian-kajian kritis tentang eksistensi universitas kita sebagai suatu institusi "culture-conserving", "culture-creating"; dan “civilizing institution”; tentang sejarah kelahirannya dan cara ia mengorganisasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya; tentang bagaimana ia membangun hubungannya dengan masyarakat tempat ia menjadi bagiannya; tentang sumbangan yang telah dan akan diberikan bagi perkembangan kemanusiaan; tentang kendala-kendala yang menghalangi kebebasan universitas untuk mengungkapkan fungsinya; dan di atas semua itu, tentang kesyahihan asumsi-asumsi yang mendasari perkembangan berbagai disiplin keilmuan yang dikembangkannya serta bagaimana asumsi-asumsi yang mereka anut berkaitan satu dengan yang lain dan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. 24. Fungsi kedua, yang juga sangat penting bagi aktualisasi misi universitas berkaitan dengan kajian-kajian sistematis tentang isu-isu kosmologi. Fokus perhatian yang harus menjadi obyek kajiannya adalah mengungkapkan pemahaman yang utuh dan bulat tentang kosmologi dunia yang dibangun dari beragam informasi yang diperoleh dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab harus muncul dari upaya-upaya untuk mengkaitkan apa yang diperoleh dari kajian-kajian kemanusiaan dengan apa yang diperoleh dari kajian-kajian ilmu psikologi, kajian-kajian ilmu sosial, dan kajian-kajian ilmuilmu alam. Fungsinya yang ketiga, bertalian dengan kajian-kajian yang secara khusus dan sistematis dirancang untuk melakukan analisa tentang beragam bentuk krisis yang terjadi pada tingkat nasional dan global. Berbagai informasi tentang hal itu memang sudah menjadi perhatian dari berbagai disiplin ilmu 11 pengetahuan, akan tetapi semua itu masih belum terintegrasi ke dalam suatu institusi yang secara khusus berusaha memperoleh pengetahuan yang utuh dan bulat mengenai seluruh persoalan yang sedang dialami umat manusia, dan bagaimana informasi-informasi tersebut berkaitan satu sama lain. 15. Fungsi kelembagaan universitas ketiga yang juga perlu dikembangkan menyangkut pengembangan sistem administrasi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi pada tingkat universitas untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk merencanakan dan mengembangkan kemampuan dan minat akademik dan profesional lintas disipliner yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan global yang semakin berat di masa depan. Yogyakarta; 11 November 2003. DAFTAR PUSTAKA Bessis, Sophie. 2003. Western Supremacy: The Triumph of an Idea?, London & New York: Zed Books. Daly, Herman E. and John B. Cobb, Jr. 1989. For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. Boston: Beacon Press. Etzkowitz, Henry and Ronald M. Glassman. 1991. The Renascence of Sociological Theory: Classical and Contemporary, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc. Gelinas, Jacques B. 2003. Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, London & New York: Zed Books. Heidegger, Martin. 1977. “Modern Science, Methaphysics, and Mathematics”, dalam Krell, David F. Martin Heidegger Basic Writings: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964), London and Henley: Routledge & Kegan Paul. Kymlycka, Will. 1999. Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Clarendon Press. Kline, Stephen Jay. 1995. Conceptual Foundations for Multidisciplinary Thinking, Stanford, California: Standford University Press. 12 Martinez-Alier, Juan. 1995. “The Socio-ecological Embeddedness of Economic Activity: The Emergence of Transdisciplinary Field”, dalam Egon Becker and Thomas Jahn, Sustainability and Environmental Considerations Into Theoretical Reorientation, Zed Books. Noam, Eli M. 1995. “Electronics and the Dim Future of the University”, dalam Science, Vol. 270, pp 247-249. Robertson, Robbie. 2003. The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness, London dan New York: Zed Books Tehranian, Majid. 1999. Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse, Linne Rienner Publishers. _______________. 1996. “The End of University”, reproduced with permission by Taylor and Francis, Inc, http:/www.routledge-ny.com. Truzi, Marcello. 1974. Verstehen: Subjective Understanding in the Social Sciences, Reading, Massachusetts: Addison-Westly Publishing Company. -------------------- 13