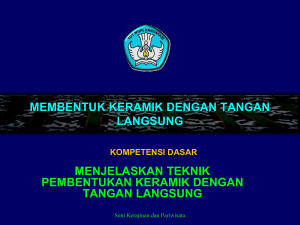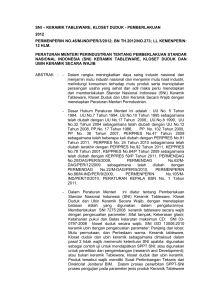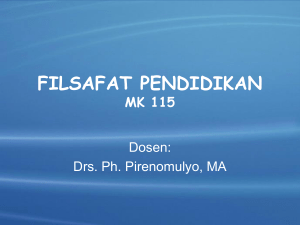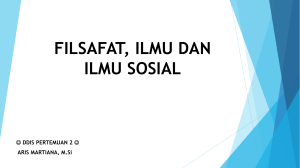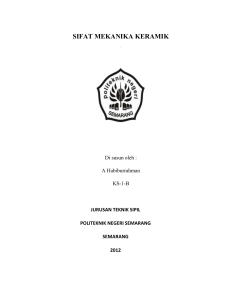Pertanyaannya: apakah seni di kebudayaan Timur dan Afrika tak
advertisement

KEBUDAYAAN DAN UPAYA MENJADI ABADI Oleh Ahmad Yulden Erwin Pengamat Budaya, Penyair, Kritikus Sastra dan Seni Rupa Gilgames berjumpa dengan Utnapishtim (Dewa Dunia Bawah atau Dewa Alam Kematian) dan mengisahkan kepada Gilgamesh tentang banjir besar yang menenggelamkan bumi. Utnapishtim dengan enggan memberikan kepada Gilgames kesempatan untuk hidup abadi. Ia berkata bila Gilgames dapat bertahan tidak tidur selama enam hari dan tujuh malam, maka Gilgames akan hidup abadi. Namun, Utnapishtim menyuruh istrinya untuk memanggang roti dan diberikan kepada Gilgamesh. Akibatnya Gilgamesh jatuh terlelap setelah selesai menyantap roti itu, sehingga Gilgames tidak dapat menyangkal kegagalannya. Ketika Gilgames terbangun, Utnapishtim menceritakan kepadanya tentang tanaman yang terdapat di dasar laut. Bila Gilgames memperoleh tanaman itu dan memakannya, maka ia akan menjadi muda kembali. Gilgames memperoleh tanaman itu, tetapi ia tidak segera memakannya karena ia ingin berbagi kepada orang-orang tua di negeri Uruk. Ia meletakkan tanaman itu di tepi sebuah danau sementara ia mandi, dan tanaman itu dicuri oleh seekor ular. Setelah gagal dalam kedua kesempatan itu, Gilgames kembali ke Uruk, dan ketika ia melihat dinding-dinding kerajaannya yang begitu besar dan kuat, ia mengagumi karya abadi manusia yang fana ini. Gilgames pun menyadari bahwa cara makhluk fana untuk mencapai keabadian adalah melalui karya peradaban dan bekerja membangun kebudayaan. —Parafrasa tabula 11 dari EPIK GILGAMESH Epik Gilgames menurut hasil penelitian arkeologis merupakan puisi pertama dalam bentuk epik yang ditulis oleh manusia dan masih ada hingga saat ini dalam bentuk tabula (lempengan tanah liat yang telah membatu). Parafrase Epik Gilgamesh di atas diambil dari versi tertua Epik Gilgamesh, pada masa Dinasti ketiga Ur (sekitar 2150 2000 SM) di Babilonia (sekarang Irak dan Iran). Dibuka dengan kalimat: "Ia yang telah melihat kedalaman" (ša nagbu amāru), dan diakhiri dengan kesadaran dari Gilgamesh setelah kembali dari Dunia Bawah (alam kematian) bahwa keabadian manusia tidak terletak pada tubuhnya, tetapi pada karya peradabannya, pada kebudayaannya. Seperti karya para penulis Epik Gilgames sendiri, yang tetap abadi, melintasi 4000 tahun lebih peradaban manusia di muka bumi. Seolah para penyair yang menulis atau menyusun Epik Gilgames itu hendak berkata kepada manusia dari masa ke masa: "Berkaryalah, menciptalah, menulislah dengan seluruh pikiran dan hatimu, dengan bersungguh-sungguh, dengan cinta yang penuh, karena hanya itulah yang mampu membuatmu abadi menghadapi keterbatasan tubuh." Saya pikir Epik Gilgamesh merupakan metafora puitik pertama yang pernah ditulis manusia tentang kesadaran budaya. 1 I. PEMAHAMAN UMUM TENTANG KEBUDAYAAN Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin “Colere”, yaitu mengolah atau mengerjakan—bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Secara umum pengertian kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk berpikir, sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggota di dalam satu kebudayaan dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. 1. Pengertian Umum Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan seharihari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, upacara religi, karya seni, dan teknologi yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 2 2. Unsur-Unsur Kebudayaan Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain: 1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: o alat-alat teknologi o sistem ekonomi o keluarga o kekuasaan politik 2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang membentuk kebudayaan, yaitu: o sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya o organisasi ekonomi o alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama) o organisasi kekuatan (politik) 3. C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal (universal categories of culture) yaitu: o bahasa o sistem pengetahuan o sistem teknologi dan peralatan o sistem kesenian o sistem mata pencarian hidup o sistem religi o sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan 3. Wujud dan Komponen Kebudayaan Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan (Wujud Ideal) Wujud ideal budaya adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak—tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan atau buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Aktivitas (Tindakan) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati, dan didokumentasikan. Artefak (Karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua orang dalam masyarakat. Artefak berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu dan yang lainnya tidaklah bisa dipisahkan. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. 3 3. Hubungan di antara Komponen Kebudayaan Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Ada tiga faktor yang dapat memengaruhi perubahan sosial: tekanan kerja dalam masyarakat, keefektifan komunikasi, dan perubahan lingkungan alam. Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam kebudayaan. 4. Penetrasi Kebudayaan Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4.1. Penetrasi Secara Damai (penetration pasifique) Penerimaan kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh dari kebudayaan baru itu pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, atau sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. 4.2. Penetrasi dengan Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah Indonesia. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. 5. Cara Pandang Terhadap Kebudayaan Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan "budaya" yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang "budaya" ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerahdaerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai "peradaban"—konsepsi dalam kata “peradaban” seringkali dilawankan dengan konsep "alam". Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Dalam prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang "elit", seperti misalnya memakai baju yang berkelas (fashion), fine art, atau mendengarkan musik klasik. Sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui dan ikut serta dalam aktivitas-aktivitas di atas. 4 Sebagai contoh, jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang "berkelas", elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan, dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah "berkebudayaan". Orang yang menggunakan kata "kebudayaan" dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. Mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma serta nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang "berkebudayaan" disebut sebagai orang yang "tidak berkebudayaan"; bukan sebagai orang "dari kebudayaan yang lain." Orang yang "tidak berkebudayaan" dikatakan lebih "asli" atau "alami". Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap "tidak elit" dan "kebudayaan elit" adalah sama, masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Selama Era Romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme, mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam "sudut pandang umum". Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara "berkebudayaan" dengan "tidak berkebudayaan" atau kebudayaan "primitif." Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama dan, dari evolusi itulah, tercipta kebudayaan. Pada tahun 50-an, subkebudayaan—kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya—mulai dijadikan subjek penelitian oleh para ahli sosiologi. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki subkebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya subkultur disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas sosial, agama, pekerjaan, pandangan politik, dan gender. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa. Beberapa cara itu antara lain: Monokulturalisme: Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. Leitkultur (kebudayaan inti): Sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. Melting Pot: Kebudayaan imigran/asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. Multikulturalisme: Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing sambil berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk. 5 II. HAKIKAT KEBUDAYAAN “Apakah sebangsamu akan kau biarkan terbungkuk-bungkuk dalam ketidaktahuannya? Siapa bakal memulai kalau bukan kau?” ― Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah Seni, sains, dan spiritualitas senantiasa masuk "menemu" ke inti, ke hakikat, ke dasar segala sesuatu. Ini yang membedakannya dari teknologi, hiburan populer, dan religiusitas massa. Yang inti pada akhirnya memang hanya bisa membuka rahasia. Yang massal kerap digunakan memanipulasi massa. Yang inti memang "tak tahu apa-apa" dan tak punya kepentingan sama sekali untuk berkuasa. Yang massal selalu merasa mengetahui hal yang paling dibutuhkan manusia, dan oleh itu merasa berhak menguasai sebanyak mungkin pikiran massa, demi mempertahankan jejaring kuasanya. Yang inti, semesta itu, hanya ada. 1. Epistemologi dan Episteme Aristoteles, filsuf Yunani kuno, membuat tiga kategori tentang pengetahuan manusia, yaitu: Episteme, Phronesis, Techne. Kategorisasi tiga jenis pengetahuan ini dikemukakan oleh Aristoteles sekitar 2400 tahun lalu dalam bukunya "The Nichomachean Ethics". "Episteme" oleh Aristoteles dikategorikan dalam konteks logika atau pengetahuan intelektual (khususnya geometri atau matematika pada waktu itu). "Techne" oleh Aristoteles dikaitkan dengan seni (tetapi maksudnya waktu itu adalah seni kerajinan tangan yang berguna dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya seni tembikar)--pada masa kini dikaitkan dengan pengetahuan tentang keterampilan teknis-dan konsep inilah yang kini menjadi akar dari kata "teknologi". "Phronesis" dimaknai oleh Aristoteles sebagai pengetahuan praktis terkait kehidupan sehari-hari manusia dan hal ini dihubungkan dengan etika. Meski dibagi ke dalam tiga kategori maksud Aristoteles sebenarnya adalah mencari dasar "pertama" bagi pengetahuan manusia di dalam realitas yang nyata ini (bertolak belakang dengan pandang idealistik dari Plato yang menganggap dasar dari filsafat berakar tidak di dunia inderawi tetapi pada realitas suprainderawi). Artinya, ketiga kategori "pengetahuan" yang dibuat oleh Aristoteles itu berakar pada prinsip "realis", yaitu prinsip korespondensi, A = A, atau, idealitas = realitas, atau, ungkapan (proposisi) = fakta inderawi. Pandangan Aristoteles ini pada abad ke-18 dikritik oleh Immanuel Kant, dengan prinsipnya yang menyatakan bahwa prinsip korespondensi itu tidak sepenuhnya benar, dan menyatakan bahwa pengetahuan kita tidak dapat mengenali hakikat dari bendabenda itu sendiri. Apa yang kita kenal tak lain adalah apa yang ada dalam wilayah pengetahuan kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan tak pernah sampai pada hakikat bendabenda itu (das ding an sich). Termasuk kategorisasi tiga jenis pengetahuan sebagai "episteme, phronesis, dan techne" oleh Aristoteles itu juga keliru bila bersandar pada prinsip korespondensi semata. Dengan demikian Kant menjadi filsuf kritis pertama dalam epistemologi atau dikenal sebagai "rasio kritis" yang mengkritik dengan tegas tiga jenis pengetahuan manusia yang bersandar pada prinsip korespondensi semata, namun pandangan Kant tidak sama dengan konsep rasio holistik yang suprainderawi dari Hagel atau logos idealistik dari Plato. Kant menulis tiga bahasan yang merupakan "kritik" atas tiga kategorisasi pengetahuan dari Aristoteles di atas, yaitu "Kritik atas Rasio Murni (Episteme)", "Kritik atas Rasio Praktis (Techne)", dan "Kritik atas Penilaian" (Phronesis). Atas "kritik" Immanuel Kant inilah kelak timbul prinsip "koherensi" yang menjadi landasan bagi logika simbolis dan matematis dari Bertrand Russel. Juga, prinsip pragmatisme yang menjadi akar kebudayaan pop di USA. 6 Dan pada pertengahan abad ke-20, Michel Foucault, sang filsuf postmodernisme dari Prancis, dalam bukunya "The Order of Things" meredefinisikan kembali konsep episteme, tidak hanya terkait sebagai pengetahuan rasional (intelektual), tetapi keseluruhan pengetahuan manusia (termasuk seni, etika, laku hidup sehari-hari), mirip dengan pendapat Thomas Kuhn tentang paradigma--hanya saja diperluas oleh Foucault mencakup seluruh sistem pengetahuan masyarakat dalam satu zaman. Karena itulah, menurut Foucault, episteme bukan sekadar kategorisasi bentuk pengetahuan yang dikaitkan dengan dengan teori korespondensi atau koherensi untuk menentukan benar atau salah, baik atau jahat, indah atau buruk, melainkan juga memiliki tendensi dan selalu terkait dalam konteks politik. Episteme dalam pengertian Foucault merupakan "wacana-kuasa" untuk menentukan hal yang dianggap sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, kebaikan atau kejahatan, kegilaan atau kewarasan, dalam konteks kepentingan politik penguasa atau masyarakat dominan pada jamannya. Contoh: buku-buku motivasi itu menurut pengertian Foucault dilandasi oleh satu episteme juga--yaitu episteme biner tentang "orang sukses" dan "orang gagal" menurut ukuran kapitalistik misalnya. Sementara Richard Rorty, filsuf postmodernisme dari USA yang terpengaruh oleh filsafat pragmatisme, berpendapat bahwa tidak ada prinsip-prinsip yang bersifat universal, dan ia juga menentang usaha masa Aufklarung untuk menemukan dasar rasional bagi pengetahuan manusia seperti pada era klasik di Eropa Barat. Di sini, Rorty mengambil posisi etnosentris radikal. Baginya, pemikiran setiap manusia ditentukan oleh bahasa apa yang dipelajari orang tersebut. Bahasa di sini dipahami sebagai perwujudan budaya tertentu, pandangan dunia tertentu, kepercayaan, dan nilai-nilai tertentu. Akan tetapi, kehadiran seorang manusia di budaya tertentu bersifat kebetulan, sebab tidak ada orang yang dapat memilih di mana ia dilahirkan. Oleh karena itu, Rorty berpendapat tidak ada budaya atau nilai-nilai yang paling benar dan berlaku universal. Budaya atau nilai-nilai apapun hanya membantu pengembangan diri seorang manusia. Jadi apa yang dimaksud oleh Rorty sebagai "bahasa" itu sebenarnya adalah semacam "episteme" (minus epistemologi rasional). Episteme Rorty adalah episteme yang plural dan bukan episteme monistik. Jika hendak diringkas sari dari epistemologi modern, maka akan berbentuk pernyataan berikut ini: “p ∧ - p adalah sebuah bentuk kontradiksi, tetapi p V - p adalah sebuah tautologi.” Epistemologi saat ini tidak bisa menerima kontradiksi sebagai sebuah proposisi yang valid. Tetapi seni, khususnya seni modern atau kontemporer, sejak awal abad ke-20 sudah dapat menerima kontradiksi sebagai sebuah prinsip seni yang valid dengan munculnya konsep jukstaposisi (menyejajarkan dua hal yang bertentangan dalam ruang-waktu yang sama). Apakah proposisi yang bersandarkan pada properti kebenaran seperti prinsip korespondensi, koherensi, dan atau pragmatisme itu selalu lebih "episteme" daripada jukstaposisi? Seluruh basis dari epistemologi modern dibangun oleh tautologi-biner. Ini jelas sebuah sistem yang tertutup, sebuah sistem apriori yang menolak relasi dengan sistem lainnya. Karena itulah epistemologi modern tak bisa melogikakan sebuah sistem terbuka atau sistem khaotik yang unsur-unsur dan relasi di dalam sistem itu lebih dari dua variabel. Epistemologi modern adalah sebuah model yang jauh dari fakta dan atau pengalaman manusia--sebuah model epistemologi yang justru melanggar prinsip fundamental dari epistemologi modern itu sendiri, yaitu: prinsip korespondensi. Bayangkan, jika dunia ini semata-mata diisi oleh Anda dan saya. Tak ada apa pun kecuali Anda dan saya. Jika Anda ada, maka saya harus tiada--begitu sebaliknya. Dan kebermaknaan dari tautologi-biner itu selalu monistik--Anda dan saya tidak bisa keduanya benar, hanya ada satu kebenaran yang benar, jika saya benar maka Anda harus tidak benar. Hanya ada Anda dan saya--dia, orang ketiga itu, dianggap tak pernah ada. Tak pernah ada relasi untuk tiga hal, dan karenanya tak ada kebenaran kedua atau ketiga dan seterusnya, hanya ada satu kebenaran. Model tautologi-biner dari epistemologi modern, jika ditinjau dalam konteks pengalaman dan fakta sehari-hari, justru adalah "argumentum ad absurdum" itu sendiri. 7 Memahami dengan baik tentang konsep epistemologi dan sejarah epistemologi dunia itu menjadi penting, seperti pendapat pendiri bangsa ini, Muhammad Hatta dan Tan Malaka, agar bangsa Indonesia mampu berpikir dengan benar dan tidak terjebak oleh sesat pikir atau diombang-ambingkan oleh episteme "kolonialis" yang mau memanfaatkan ketakmampuan berpikir logis bangsa ini untuk kepentingan kuasanya. Jadi, pahami episteme atau epistemologi atau konstruksi logis dari satu hal, maka kita akan bisa melampaui segala kulit-kulitnya, melampaui sesat pikirnya, melampaui banjir informasi yang sengaja diciptakan oleh segelintir penguasa episteme--sebelum akhirnya kita melampaui konsep episteme itu sendiri. 2. Logika Dharmakirti Augustus De Morgan, seorang filsuf logika dan matematikawan dunia, pernah menulis pada tahun 1860 tentang pentingnya logika India: "Dua peradaban yang telah membangun ilmu matematika, yaitu orang-orang dari bahasa Sansekerta dan bahasa Yunani, keduanya secara independen telah membentuk sistem logika dunia." Asal muasal logika modern, misalnya aljabar logis dan logika matematika, seperti yang diperkenalkan oleh para filsuf logika dan matematikawan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Inggris, ternyata bersumber dari sistem logika di India yang telah berkembang sejak abad ke-5 masehi. Seperti diketahui bahwa logika modern yang bertumpu pada aljabar logis itulah yang menjadi dasar bagi perkembangan bahasa pemrogaman komputer sehingga menimbulkan teknologi informasi seperti internet dan artificial intellegence (AI) saat ini. Salah satu tokoh yang terkenal sebagai pendiri logika di India adalah bernama Dharmakirti yang hidup antara 600 - 670 masehi di India, sejaman dengan masa Sriwijaya awal. Kabarnya Dharmakirti adalah seorang pangeran dari wangsa Sailendra di Sriwijaya yang belajar dan menetap di India Selatan. Ia kemudian menjadi seorang guru Budhisme Esoteris Vajrayana dan mengembangkan ilmu logika di perguruan tinggi Nalanda. Karya-karya Dharmakirti ini masih tersimpan sebagai teks Budhisme Tibet hingga saat ini. Dharmakirti sebagai ahli logika berbeda dengan Dharmakirti Swarnadwiphi yang hidup pada abad ke-10 di Sriwijaya (seorang guru spiritual yang mengembangkan ajaran Bodhicitta dan masih menjadi salah satu ajaran utama dalam Budhisme Esoteris di Tibet), namun keduanya dilahirkan di tanah yang sama yaitu tanah Sriwijaya. Catatan sejarah dari Yijing pada abad ke-7 masehi yang pernah singgah ke kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa pada abad ke-7 masehi Sriwijaya merupakan pusat peradabadan ilmu dan spiritual yang besar hingga orang-orang dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk menimba ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Bayangkan, jika seorang seperti Dharmakirti pada abad ke-7 masehi saja telah mengajarkan ilmu logika yang kelak menjadi dasar dari teori set, logika simbolis, aljabar predikat, dan linguistik modern (sebagai dasar dari bahasa pemrograman komputer saat ini) seperti yang dipelajari dan "ditiru" Charles Babbage, Augustus De Morgan, dan khususnya George Boole—lantas mengapa kita sampai tidak tahu sejarah ini? Jawabnya sederhana: Karena sampai sekarang kita tidak menerjemahkan buku-buku "kanonik" dunia sehingga kita tidak bisa belajar langsung dari berbagai sumber yang telah membangun "episteme" modern saat ini—seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada abad ke-19. Kita seperti orang yang "dibuat" untuk mengalami lupa ingatan akan kekuatan "episteme" dari peradaban kita sendiri, sehingga kita dapat terus menerus "diperbudak" dan atau minimal dapat awet cuma dijadikan sebagai "bangsa kuli". 3. Logika Seni Apakah seni tak berdasarkan pada epistemologi? Jika ada yang berpikir bahwa seni tak ada hubungannya dengan epistemologi, maka hal itu menunjukkan ia tak paham filsafat estetika sebagai bagian dari filsafat aksiologi. Dasar dari filsafat aksiologi (etika dan estetika) selalu bertolak dari epistemologi tertentu. 8 Jika tak ada epistemologi untuk estetika, untuk seni, untuk puisi--maka tak ada alasan untuk mencipta karya seni, tak ada landasan bagi semua teori estetika, dan karya seni juga tak memiliki makna. Karya seni dan estetika akan menjadi misteri yang tak terjelaskan, tak bisa dipahami, dan sekaligus tak bermakna. Namun, benarkah seni tak memiliki episteme? Apakah episteme sama dengan epistemologi? Ketika episteme dijelaskan, diuraikan, diwacanakan, dan digunakan, maka ia menjadi epistemologi. Namun, ada banyak lagi jenis epistemologi yang belum diketahui. Tentu saja, belum diketahui bukan berarti setara dengan tidak diketahui. Kebeluman bukanlah ketiadaan, sebab kedua hal itu berada dalam kategori yang berbeda. Benarkah karya seni adalah sebuah "misteri", sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang harus dikeluarkan dari wilayah epistemologi? Apakah "misteri" itu—jika dirumuskan dengan bahasa formal logika—merupakan sebuah bentuk pernyataan kontradiksi ataukah hal itu justru sebuah pernyataan khaotik karena relasinya dibangun oleh tiga variabel atau lebih? Selama ini "misteri" dikeluarkan dari wilayah epistemologi karena dianggap sebagai pernyataan kontradiksi atau paradoks. Dalam bahasa mudahnya, kira-kira begini: "Karya seni tak bisa dilogikakan." Pernyataan di atas jelas menunjukkan dan, sadar atau tak sadar, mendukung epistemologi modern tentang kontradiksi sebagai bukan bagian dari epistemologi dengan menganggap karya seni sebagai konsep yang tak bisa dijelaskan, tak bisa diuraikan, dan tak bisa dipahami— sebuah "misteri" yang melampaui epistemologi manusia. Seni realisme, contohnya, bertolak dari prinsip korespondensi dalam epistemologi klasik, yang dalam istilah estetika dikenal sebagai mimetik (tiruan dari alam)—suatu konsep estetika yang dicetuskan oleh Aristoteles. Estetika seni realisme percaya bahwa seni yang indah haruslah meniru alam. Prinsip memetik ini bertolak dari prinsip korespondensi di dalam epistemelogi (A = A, atau idealitas sama dengan realitas). Di dalam seni puisi dikenal aspek prosodi atau irama yang disebut metrum. Konsep metrum pada puisi Barat pertama kali dicetuskan oleh sastrawan Yunani, Horace (65 - 8 SM), di dalam bukunya Ars Poetica yang kelak menjadi standar bagi sintaksis puisi klasik dan romantik di Eropa pada abad pertengahan. Oleh Horace aspek metrum ini dianggap merupakan tiruan dari "irama alam" atau dikenal sebagai metrum natural. Sedangkan seni nonrealis (utamanya seni modern) bertolak dari prinsip koherensi di dalam epistemologi. Prinsip koherensi menyatakan bahwa dasar dari seni bukanlah meniru alam, tetapi bertolak dari konvensi yang dibuat oleh manusia berdasarkan satu teori atau beberapa teori tertentu (bisa sains atau spiritualitas). Misalnya, simbolisme bertolak dari spiritualitas yang berlandaskan pada prinsip kontradiksi atau paradoks. Surealisme bertolak dari teori psikoanalisa dan Marxisme. Impresionisme dalam seni rupa bertolak dari teori optik. Ekspresionisme dan fauvisme bertolak dari teori psikologi warna dan spontanitas emosi pada seni lukis pascaimpresionisme. Jadi, prinsip seni nonrealisme bukanlah mimetik tetapi berlandaskan kepada teori sains atau spiritualitas yang telah disepakati sebelumnya. Inovasi dalam konteks seni merupakan bantahan atau mengembangkan teori yang ada sebelumnya dengan membuat teori seni baru, misalnya kubisme dari Pablo Picasso merupakan bantahan terhadap teori satu perspektif dari seni impresionisme. Karya seni, secara analogi, seperti sebuah sistem terbuka yang kompleks dan berada di tepi khaos. Bisa jadi, teori khaos adalah semacam epistemologi dari cinta. Sebuah epistemogi dari sistem kompleks yang khaotik adalah sebuah gerak umpan balik yang berada dalam pemusatan oleh atraktor asing. Ia bukanlah potret, tetapi ia lebih mirip sebuah film. Epistemologi terus bergerak, terus melampaui gambaran sederhana tentang properti korespondensi atau koherensi atau pragmatisme dari kebenaran. Pertanyaannya: apakah seni di kebudayaan Timur dan Afrika tak bertolak dari epistemologi atau episteme tertentu? 9 4. Seni dan Misteri Keesaan yang Sehari-Hari Bahasa Pali: "Eso va maggo natthabbo dassanassa visuddhiya." Bahasa Indonesia: "Inilah Jalan, tiada Jalan lain untuk benar-benar Melihat dengan Terang." Kata "esa" dalam bahasa Indonesia berasal dari bentuk penulisan bunyi kata "eso" (esā) dalam bahasa Pali di India Tengah pada masa lalu. Bahasa Pali adalah bahasa yang digunakan dalam teks-teks Buddhis awal. Arti kata "esa" dalam bahasa Pali, bukanlah satu, tetapi "ini", "kehadiran sesuatu atau seseorang", "udara", dan "itu". Konsep "esa" dalam arti "ini" adalah kehadiran serentak dalam keseluruhan perspektif penglihatan di dalam ruang-waktu pada saat ini: "kini yang di sini". Arti kata "esa" juga tak bisa dimaknai sebagai "kekosongan", karena dalam bahasa Pali kata untuk kekosongan adalah "suññatta". Pemaknaan "esa" menjadi kata "satu" sebagai bilangan seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan reduksi yang keliru dalam konteks semantik. Karena makna kata satu dalam bahasa Pali adalah "eka", bukan "esa". Jadi, dalam konteks semantik, secara marfologis, tafsir yang mendekati kebenaran dari kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah "Keilahian Yang Maha Hadir (serentak) Di Sini dan Saat Ini". Terkadang, apa yang disebut "misteri" atau yang tak terkatakan atau yang ajaib hanyalah soal "keserentakan". Dalam bahasa Latin, kata "serentak" ini ditulis sebagai "simul" yang menjadi muasal kata "simultaneously" dalam bahasa Inggeris, atau "synchróno̱s" dalam bahasa Yunani. Kata ini juga sinonim dengan kata "una" (latin) yang menjadi indung kata "uni" atau "one" dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Bengali kata "serentak" ditulis sebagai kata "ekayoge" atau "eka satha" dalam bahasa India dan Nepal. Dalam bahasa Indonesia kata "serentak" itu mungkin lebih kena makna dengan kata "esa". Konsep "keserentakan" atau ke-esa-an jika diterapkan dalam persepsi indrawi, misalnya "melihat", akan menghasilkan konsep supraindrawi. Kata "melihat" (dalam satu perspektif tertentu) adalah soal persepsi indrawi (mata) biasa. Tetapi, ketika engkau dapat "serentak" melihat dari berbagai perspektif dalam satu ruang-waktu tertentu, maka persepsi indrawi itu akan menjadi supraindrawi—dan konsep tentang "maha melihat" pun tercipta. Keserentakan mungkin kata ganti yang paling mirip tentang konsep "maha". Sebenarnya, benda apa pun yang hadir di ruang-waktu ini selalu hadir dalam keserentakan, utuh merangkum seluruh perspektif, hadir sebagai Yang Maha Nyata. Yang jadi soal adalah bahwa persepsi inderawi kita—atau mungkin "episteme" kita— membatasi kehadiran seluruh perspektif tersebut hanya dapat dipersepsi dari satu perspektif saja. Meski pada kenyataannya, apa pun benda yang hadir di hadapan kita, adalah seperti sebuah gema yang bergaung ke segala arah di dalam ruang-waktu dan tak pernah bergaung ke satu arah saja, atau umpama sebuah riak yang bergerak ke segala arah di atas permukaan telaga dan tak pernah bergerak ke satu arah saja. Keesaan itu ada sebagai "lingkungan" kita, sebagai latar bagi keberadaan kita. Segala sesuatu adalah ajaib, karena segala sesuatu hadir secara serentak, karena segala sesuatu itu esa. Seperti lukisan multiperspektif (kubisme) karya Pablo Picasso, seorang pelopor seni lukis modern dunia, yang berjudul “Perempuan Duduk (1936)” di bawah ini. 10 Pertanyaannya: Apakah latar lukisan, di belakang “perempuan duduk kubistik” itu, menonjol keluar (membentuk semacam benda padat) atau masuk ke dalam (membentuk semacam ruang) pada lukisan karya Pablo Picasso di atas? Jawab: kedua-duanya. Latar itu terlihat sebagai benda padat sekaligus ruang. Dua hal yang menurut epistemologi modern dianggap sebagai kontradiksi, justru dihadirkan sebagai latar yang "serentak"— benda padat itulah ruang dan ruang adalah benda padat. Kebenaran dalam lukisan Picasso itu tidak lagi berupa perspektif tunggal, monistik, tetapi telah menjadi multiperspektif—telah menjadi plural sekaligus esa, Bhineka Tunggal Ika. Sekarang sedikit-banyak kita mulai memahami, apa sebenarnya "episteme"—atau lebih tepat epistemologi--dari estetika modern atau kontemporer itu. Dengan prinsip keesaan—sebagai presensi, sebagai konsep "keserentakan" estetik terkini—maka sekarang estetika kontemporer pada abad ke-21 memiliki landasan "objektifnya" tanpa mesti mendasarkannya kepada psikologisme, seperti konsep estetika surealisme yang melandasi dirinya dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud. Prinsip keesaan berbeda secara mendasar dengan konsep psikologisme dalam memahami keserentakan. Keserentakan estetik, dalam perspektif prinsip keesaan justru hadir di dalam realitas sehari-hari sebagai evidensi, sebagai bukti keberadaan, dan bukan hadir dalam alam mimpi seperti konsep estetika surealisme. 5. Bagaimana Memahami Epistemologi Presensi Di dalam dunia sehari-hari, di dalam peristiwa, tak ada subjek atau objek, yang ada hanyalah predikat, proses itu sendiri. Tetapi, oleh sebab episteme kita sudah terbentuk dalam kerangka tautologi-biner, dalam prinsip urut-urutan kausalitas, maka terciptalah subjek dan objek sebagai dua pilar proposisi, di mana fungsi predikat hanyalah untuk menjelaskan subjek atau objek, hanya menjadi subordinat dari fungsi subjek atau objek. Ketika tautologi-biner itu dicabut sebagai satu-satunya pondasi dalam epistemologi, maka yang hadir kemudian adalah keserentakan predikat—tanpa subjek, tanpa objek. Ini adalah dasar dari epistemologi seni, epistemologi puisi, dan tak ada satu pun filsuf modern atau pakar logika di dunia yang pernah berpendapat tentang hal ini sebelumnya. 11 Kenapa hal yang fundamental begini justru terabaikan? Itu karena sejarah epistemologi dan logika adalah sejarah tautologi biner dan kriteria kebenaran monistik-bukan keesaan, bukan keserentakan. Sekarang, ketika para pakar "artificial intellegence" terbentur untuk memahami sistem berpikir manusia, akibat terkurung dalam epistemelogi monistik, maka mereka suka atau tidak suka harus memahami "logika seni". Puisi kuno berjudul "Adi Shakti" (teks aslinya ditulis dalam bahasa Sansekerta) merupakan cermin dari episteme atau kesadaran akan keesaan segala sesuatu. Epistemologi keesaan menyadari keserentakan segala sesuatu sebagai kebenaran, kehadiran segala sesuatu sebagai pancaran "keajaiban" dari yang sungguh nyata di dalam kehidupan sehari-hari, keajaiban yang memelihara dan tidak ingin menguasai: “Alam adalah kita, kita adalah alam.” ADI SHAKTI Sanskrit: "Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, namo, namo. Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, namo, namo. Prithum Bhagvati, Prithum Bhagvati, Prithum Bhagvati, namo namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, namo, namo." English: "First force of all creation, to You I bow. Divine force, everywhere, to You I bow. Creative force, primal force, to You I bow. Rising up, Divine Mother, to You I bow." Presensi begini selalu ada di dalam dan di luar diri kita tanpa jarak—epistemologi monistiklah yang menciptakan jarak itu, membuat kesadaran menjadi sistem tautologibiner yang tertutup. Epistemologi keesaan jelas berbeda dengan epistemologi monistik yang menguasai dunia saat ini, yang memandang kebenaran sebagai "milik" tunggal sang manusia yang mengetahui, penguasa episteme, sementara alam hanyalah musuh atau minimal budak yang mesti melayani kepentingan manusia. Epistemologi monistik telah memilih menghancurkan latar yang memungkinkan keberadaan manusia, alam itu, yang berarti telah memilih untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Kita telah terilusi oleh epistemologi monistik yang tertutup, tautologi-biner yang memencilkan diri kita dari lingkungan sekitar kita, dari alam sebagai "latar" yang memungkinkan dan memelihara keberadaan kita sebagai manusia, dan dari manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Inovasi sebagai Sarana Kreativitas bagi Kemajuan Budaya Tak ada kreativitas tanpa inovasi. Melakukan kerja kreatif yang menuntut inovasi memang amatlah berat. Kita harus memiliki urat saraf baja, kekuatan kehendak untuk bertahan dalam tekanan, dan pantang menyerah—kecuali, jika dan hanya jika, kita sudah cukup puas menjadi medioker. Mencipta karya seni maupun sains atau teknologi adalah sepenuhnya kerja kreatif, tak ada tempat bagi yang setengah-setengah. Kreativitas dalam seni (maupun sains) tidaklah lahir dari ketidakpahaman— apalagi kengawuran. Kreativitas dalam wujud inovasi selalu lahir dari pemahaman yang mendalam akan teori dan sejarah seni yang ada. Pemahaman itu kemudian dikembangkan lebih jauh lagi atau ditentang untuk menemukan "jalan baru". Namun, jalan baru tersebut dalam sejarah seni modern dunia—begitu pun dalam sains—selalu lahir dari landasan teoritik yang kukuh; tidak pernah lahir dari kengawuran dan, apalagi, kegilaan. Bahkan seorang penganut "Dionysian" yang lunatik seperti Nietzsche, juga bertolak dari pemahaman yang mendalam akan teori-teori filsafat dan seni yang ada sebelumnya, barulah mampu melahirkan filsafat uniknya sendiri. 12 Ilmu hanya ditakuti oleh para "dewa-dewi palsu" yang bodoh—oleh sebab takut kebodohan dan prabawa palsu mereka, topeng-topeng kharismatik yang dibuat-buat untuk menipu itu, terbongkar. Kebodohan adalah salah satu syarat terpenting untuk menjual "kebohongan" dengan mudah kepada massa. Di dalam sains, sebuah teori akan bisa diujikan oleh siapa pun yang berkompeten untuk mengujinya. Bila-bila saja ditemukan kekeliruan dalam sebuah teori sains, berdasarkan metode dan teori tertentu, maka kekeliruan itu akan dibeberkan secara terbuka. Tak ada soal personal dalam pengujian itu. Seorang ilmuwan dinilai dari karyanya. Jika karyanya terbukti keliru, maka kekeliruan itu akan dibeberkan, tidak peduli apakah sang ilmuwan telah bergulat sekian puluh tahun dalam sains, sudah mendapat penghargaan sekian banyak, sudah dipuja-puji di dalam banyak majalah atau televisi. Itu disebut prinsip falsifikasi dalam epistemologi ilmu pengetahuan, satu prinsip yang membuat ilmu pengetahun menjadi dinamis, menjadi terus berkembang. Di dalam sains, teks saja sudah cukup untuk menilai kualitas karya intelektualnya. Sebuah trik pemasaran atau pencitraan personal tertentu tak akan menguatkan atau menggugurkan kualitas dari sebuah teks sains. Bagaimana dengan seni? Sama saja. Yang paling penting bagi para pelaku dan pengapresian seni di Indonesia saat ini adalah belajar memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan "inovasi". Inovasi di dalam sains atau seni, hakikatnya sama saja. Inovasi harus mampu melahirkan "tawaran baru" dengan landasan konsep yang kokoh dan dapat menggantikan konsep yang sebelumnya. Teori relatavitas Eisntein, misalnya, mampu menggantikan teori fisika Newton untuk menjelaskan fenomena alam fisik, bahkan mampu menjelaskan fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh teori fisika Newton. Jadi, Einstein tak hanya "memberontak" dengan hanya menafikan teori fisika Newton tentang asumsi adanya ruang dan waktu yang absolut, melainkan juga mengeluarkan teori baru yang bisa diuji kebenarannya dengan mengeluarkan argumen bahwa ruang-waktu itu relatif terhadap posisi pengamat. Jika tidak begitu, karya-karya seni kita tak akan bisa diapresiasi oleh dunia. III. SENI KERAMIK JEPANG: SEBUAH MODEL TRANSFORMASI BUDAYA Cawan keramik gaya raku, karya Raku Kichizaemon XV, Jepang. 13 Seni keramik Jepang itu seperti sebuah karya seni lukis dan seni patung yang digabung menjadi satu, warna dan rupa, yang bisa diletakkan dengan nyaman di telapak tangan kita. Sebuah cawan atau cangkir atau vas keramik adalah sebuah lukisan yang bisa diraba sekaligus patung yang memiliki kedalaman dan keajaiban warna. Seni keramik Jepang adalah wujud dari konsep presensionisme dalam seni. Yang rahasia dan yang sehari-hari, yang nyata dan yang tersembunyi, masa lalu dan masa depan dan masa kini--segalanya hadir serentak pada satu momen presensi yang tak tergantikan, tak dapat diulangi, sempurna dalam segala yang tak sempurna. Itulah sejatinya seni presensionisme. Wujud ideal dari seni "presensionisme", seni "keesaan", seni dari "kepaduan" unsur-unsur kosmik (tanah, air, api, kayu, angin) dan kreativitas delapan indera manusia (tangan, kaki, mata, kulit, hidung, telinga, lidah, dan pikiran), juga konsep "wabi-sabi" (keserentakan dari ketaksempurnaan dan kesempurnaan) ada pada seni keramik Jepang. Saya tertarik mendalami seni keramik kontemporer dunia, yang bersumber dari tradisi Jepang, oleh sebab spirit yang dibawa dalam seni keramik itu adalah "wabi-sabi", ketaksempurnaan dalam kesempurnaan, kerapuhan dan karat (saba), deformasi bentuk, khaos di dalam kosmos. Selalu ada "cacat artistik" yang dibawa dalam seni keramik kontemporer itu, terutama yang dibakar di tungku dengan bahan bakar kayu (anagama atau noborigama), bukan tungku atau oven listrik. Selalu ada yang tak terduga dalam keramik yang dibakar dalam suhu 1200 - 1300 derajat celcius itu, slip (dekorasi pada keramik) yang "dilukis" oleh panas api, oleh abu kayu dan arang, yang ada di dalam anagama saat pembakaran. Teknik pembakaran dengan kayu dalam suhu tinggi, seperti ditemukan dalam gaya Bizen, Shiga-raki, Hagi, atau Shino mampu menghasilkan rasa seni dalam bentuk kontemporer, meski pada dasarnya ini adalah teknik kuno yang populer pada Periode Edo (1603-1868). Teknik ini "ditiru" oleh seniman keramik Jepang pada masa itu dari seni keramik Korea dan Cina. Pada awal abad ke-20, para empu keramik Jepang modern seperti Kitaoji Rosanjin, Tomimoto Kenkichi, Hamada Shoji, dan Arakawa Toyozo mulai menggali lagi teknik pem-buatan tembikar dari masa periode Edo tersebut. Kemudian Bernard Leach dari Inggris melakukan studi keramik dengan teknik tradisional di Jepang dan memberi inspirasi bagi tumbuhnya kembali seni keramik modern di Jepang. Setelah kembali ke Inggris, Bernard Leach mulai mengembangkan seni keramik modern menggunakan teknik tradisional Jepang, Cina, dan Korea di Inggris. Bernard Leach juga adalah "potter" (seniman keramik) pertama yang memperkenalkan teknik pem-buatan cawan "Raku" ke Inggris, AS, dan negara Eropa lainnya. Sejak itu seni keramik modern Jepang mulai populer di seluruh dunia. Ada yang menarik di dalam bangkitnya kembali seni keramik Jepang pada awal abad ke-20, yang memberi inspirasi saya untuk menulis puisi-puisi baru saya sejak 2012 hingga saat ini, yaitu semangat kontemporer yang bertolak dari tradisi. Semangat itu adalah "kebebasan untuk berinovasi". Empu seni keramik Jepang yang paling disegani seperti Rosanjin Kitaoji dengan terang-terangan telah meniru teknik seni keramik Jepang dari bermacam gaya pada periode Edo, mulai dari gaya Bizen, Shigaraki, Oribe, Karatsu, Raku, Hagi, Shino, dll. Namun, seperti katanya dalam satu wawancara dengan majalah seni keramik di Jepang, ia tak hanya meniru gaya seniman keramik pada masa Edo, tetapi menangkap spiritnya, menangkap jiwa dari seni keramik Jepang pada masa lalu, dan menghadirkannya kembali pada masa modern dengan gayanya sendiri. Ia percaya bahwa spirit dari seni keramik Jepang sejak masa Edo adalah inovasi dalam estetika. Spirit itu dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap momen dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu baru, selalu tak pernah sama. Dan karenanya kefanaan itu patut disyukuri, patut dirayakan, dengan menyadari bahwa setiap hari adalah hari baik, setiap momen adalah momen keindahan, meski kehidupan sehari-hari kita jauh dari sempurna. Cacat itu, ketaksempurnaan dalam kehidupan sehari-hari, tak mesti ditolak secara psikologis, tetapi harus dilampaui. Berhenti menolak kehidupan yang tak sempurna, dan menerimanya dalam “rasa cukup”, adalah inti dari spirit wabi-sabi—kesempurnaan dalam ketaksempurnaan, 14 sekaligus inti dari seni keramik Jepang. Di dalam bentuk-bentuk keramik yang seolah terlihat "cacat", yang tak mulus, yang tak simetris, yang khaos itu, selalu ada kosmos dari keberanekaan bentuk dan, penerimaan terhadap “cacat artistik” itu, justru menimbulkan keberagaman bentuk yang tak bisa diduga—sebuah misteri dari kebebasan. Semangat inovasi yang dilandasi oleh spirit wabi-sabi itulah yang hingga abad ke21 telah diteruskan oleh para seniman keramik Jepang, seperti Ken Mihara dengan patung-patung atau pasu bunga keramik berbentuk perahu, cawan, atau bejana yang mengesankan bentuk-bentuk arkeologis dan membawa ketakterdugaan. Semangat inovasi berlandaskan tradisi itu juga diteruskan oleh para seniman keramik terkini di Inggris seperti Jennifer Lee, John Leach, Phil Rogers, dll. Di Amerika, terutama di North Carolina dan Minesotta, semangat inovasi itu juga diteruskan oleh seniman keramik seperti Warren MacKenzie, Mark Hewitt, Judith Duff, Dan Finnegan, Naomi Dalglish, dll. Dalam semangat inovasi itu, seni keramik Jepang yang dibawa ke Eropa dan AS menjadi lebih halus, karena mereka mengeksplorasi keramik berbahan porselen dengan teknik pembakaran pada tungku kayu, sehingga menghasilkan dekor alami pada dinding porselen dari deposit abu kayu pembakaran. Meski demikian, eksplorasi dan inovasi yang unik itu tetap berpegang pada spirit wabisabi, spirit saba (karat), spirit kefaanan, sebagai jiwa dari seni keramik Jepang sejak masa Edo hingga saat ini. Kehadiran seni keramik Jepang di dunia modern telah mampu menyatukan spirit Timur dan Barat, secara simultan, ke dalam aneka teknik dan gaya sebagai sebuah "seni presensionisme". Sains-seni-spiritualitas menyatu secara inovatif di dalam seni presensionisme, seperti sebuah cawan gaya "raku" di atas, sebuah kosmos alit yang tak bisa diulangi, perihal yang sampai saat ini tak mampu dibuat oleh teknologi artificial intelligence. Hanya oleh itulah seni masih berharga untuk terus dicipta dan menjadi "tanda" bagi kemanusiaan kita. Rasa saya, spirit seperti ini dapat menjadi titik tolak dari seni tradisi, seni modern, dan seni kriya kita saat ini. Seni kontemporer kita harus mencoba mencari jalan "lain", untuk hadir sebagai sebuah presensi, keserentakan dari pandangan Timur dan Barat, dari teknik Timur dan Barat, dalam bentuk-bentuk seni kita yang amat beragam. 1. Inovasi dalam Cawan Tembikar Tsukigata Cawan keramik kontemporer gaya Oni-Shino, karya Tsukigata Nahiko, Amerika Jepang. 15 Lama saya renungkan, apakah memang tak ada lagi inovasi dalam seni kontemporer? Apakah kebaharuan dalam seni sudah mati? Apakah para seniman kontemporer hanya mampu mangulang-ulang gaya seni sebelumnya, atau, paling maksimal, hanya bisa mengembangkan gaya seni pendahulunya melalui semacam kejumudan intertekstualitas? Bertahun pertanyaan-pertanyaan begitu kadang muncul kadang mengendap kadang berkitar di tengah medan renung saya akan hakikat seni. Hingga pada suatu petang, saya mengalami semacam "serendipity", merasakan "kebetulan yang manis", taktala saya tengah melihat melalui internet dan merasa-rasakan proses penciptaan tembikar karya seniman keramik modern Jepang, Tsukigata Nahiko (1923-2006). Saat itu, pelan-pelan, sambil menikmati lanskap jilatan lidah api pada satu mangkuk keramiknya, saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan soal kebaharuan dalam seni. Begini muasalnya: Adalah sejarah seni tembikar modern Jepang ditandai dengan munculnya tiga seniman keramik pelopor, yaitu: Kitaoji Rosanjin (1883-1959), Kato Tokuro (18981985) dan Arakawa Toyozo (1895-1985). Mereka diikuti oleh sejumlah seniman keramik Jepang yang membangun karya seni tembikarnya di atas pondasi ketiga pelopor itu. Para seniman keramik seperti Suzuki Osamu, Kato Kozo, Hayashi Shotaro, Wakao Toshisdada, Yoshida Yoshihiko, Ando Hidetake, Toyoba Seiya dan lainnya telah menambahkan aspek estetika modern ke dalam seni tembikar Jepang. Namun, dalam gerakan seni tembikar modern Jepang, ada dua seniman keramik yang menonjol sebagai inovator yang unik, yaitu: Tsukigata Nahiko (1923-2006) dan Kumano Kuroemon atau lebih dikenal dengan julukan "beruang dari Echizen". Karya-karya tembikar buatan Kumano Kuroemon terkenal berani menampilkan bentuk yang tak lazim. Ia menghadirkan "cacat artistik" sebagai ekspresi keindahan itu sendiri di dalam karya tembikarnya. Kumono melakukan teknik pembakaran yang ekstrim di tungku yang bersuhu hampir 1500 derajat celcius guna menghasilkan permukaan keramik yang berkilau dan sekeras kaca, menghadirkan "cacat artistik" yang tak terduga, dinamik, dan sebagian besar memunculkan warna-warna natural di alam. Karya Kumano segera dapat dikenali dari bentuk-bentuk tembikarnya yang ekstrim dibandingkan dengan karya tembikar Jepang lainnya. Sementara Tsukigata Nahiko seakan menjadi kebalikan dari Kumano yang eksplosif itu. Karya-karya tembikar Tsukigata nampak tenang, mampu menarik renung, dan seakan tengah menuntun apresiannya masuk ke dalam satu perjalanan spiritual menuju pencerahan yang tak terduga. Awalnya Tsukigata belajar dan bekerja dengan Arakawa Toyozo dan mewarisi sejumlah metode, gaya, serta teknologi pembakaran dari mentornya tersebut. Setelah bekerja dengan Arakawa, Tsukigata mulai bereksperimen dengan gaya dan metodologi pembakarannya sendiri. Kemudian ia menciptakan istilah yang sekarang terkenal sebagai Oni-Shino dan juga Oni-Iga untuk menggambarkan metode barunya tersebut. Karya tembikar yang dihasilkan dari teknik Oni-Shino akan menghasilkan perpaduan dari ekspresi alami tanah liat dan semacam lanskap alam, hal yang tak pernah terlihat di tembikar Jepang sebelum "ciptaan"-nya. Teknik Oni-Shino pada dasarnya teknik pembakaran tembikar dengan menggunakan bahan bakar kayu-kayu tertentu di dalam tungku. Pembakaran itu akan menghasilkan glasir (kilau permukaan keramik) yang alami (tanpa pewarna). Dengan melakukan pembakaran di tungku bersuhu sangat tinggi dan melalui penggunaan berbagai jenis kayu, Tsukigata mampu membangun glasir alami di tembikarnya, yang berkilau seperti kaca, ditambah dengan semacam lanskap unik yang timbul dari hasil pembakaran itu sendiri. Pendekatan teknik pembakaran menggunakan bermacam jenis kayu untuk seni tembikar adalah jalan bagi dedikasi. Sejak tahun 1950-an banyak para seniman keramik telah memilih menggunakan api gas yang lebih mudah dikontrol saat melakukan pembakaran tembikar. Namun, teknik Oni-Shino dari Tsukigata adalah sebuah jalan yang justru memangkas semua kemudahan itu. Ia memilih untuk membuat setiap tembikarnya menjadi unik karena proses pembakarannya yang tak sama, yang tak terduga, dan tingkat panasnya tak bisa dikontrol seperti saat menggunakan teknologi pembakaran api gas. 16 Setiap karya tembikar Tsukigata akan menjadi unik karena "tangan-tangan api" yang alami itu dibiarkan membentuk tembikar sesuai dengan "kehendak" sang api. Api tak lagi ada di bawah kendali manusia, tetapi secara partisipatif dibiarkan bersama sang seniman keramik mencipta sebuah karya seni tembikar yang indah. Melalui teknik pembakaran kayu untuk seni tembikarnya, Tsukigata memastikan setiap tembikar akan memiliki cerita yang berbeda, narasi yang unik, yang mampu menggetarkan persepsi penatapnya dengan kisah pergulatan seorang seniman keramik, sebuah proses yang penuh dedikasi dan kesabaran untuk membiarkan kekuatan api bekerja secara alami. Setiap cawan keramik karya Tsukigata mampu menarasikan dengan kuat bagaimana ketabahan sang seniman keramik menjalani proses penciptaan karya seninya, bagaimana mangkuk tanah liat yang basah itu pelan-pelan "diwarnai" dan diglasir oleh tangan-tangan api yang menyala, hingga akhirnya menampilkan sebuah lanskap api yang teduh pada permukaan semangkuk tembikar yang akan terus "hidup" dan menyala di dalam batin penatapnya. Sebuah seni paradoks yang sempurna. Begitulah akhirnya, saya mulai menyadari, inovasi memang selalu masih dan akan terus dimungkinkan dalam seni. 2. Estetika Mingei, Filsafat Seni Keramik Modern Jepang Piring keramik gaya mingei, karya LNT Hamada Shoji, Jepang. Filosofi seni keramik modern Jepang dibangun pertama kali oleh Yanagi Soetsu, yang dikenal sebagai filosofi "Mingei" pada tahun 1926. Pilar filosofis Mingei adalah "seni kerajinan tangan dari orang-orang biasa". Yanagi Soetsu menemukan esensi keindahan dalam barang kerajinan sehari-hari, barang-barang yang dibuat oleh pengrajin tanpa nama dan tidak dikenal. Menurut Yanagi, barang-barang kerajinan yang dibuat oleh orang-orang biasa itu ada "di luar keindahan dan keburukan". Berikut adalah beberapa kriteria Mingei terkait seni kerajinan: 1. Dibuat oleh seniman anonim—para seniman keramik gaya mingei, seperti Kawai Kanjiro di Jepang atau Warren MacKenzie di AS, pada awalnya tak pernah memberikan “mark” atau akronim namanya pada setiap kataya seni keramiknya. 2. Diproduksi dengan tangan secara massal (Shoji Hamada, pelopor seni keramik gaya mingei di Jepang, selalu mengerjakan produksi seni keramiknya secara gotongroyong dengan penduduk sekitar). 3. Murah dalam harga jualnya. 4. Dipergunakan oleh sebanyak mungkin masyarakat di sekitarnya. 5. Fungsional dalam kehidupan sehari-hari. 17 6. Merepresentasikan keunikan dari daerah tempat barang-barang itu diproduksi. Dengan munculnya estetika Mingei ini, maka Yanagi Soetsu telah menyelamatkan seni keramik Jepang, yang sebelumnya dianggap sebagai seni rendah, yang digunakan oleh rakyat jelata pada periode Edo dan Meiji, dan menghilang dengan cepat karena tingkat urbanisasi yang tinggi di Jepang pada awal abad ke-20. Yanagi Soetsu juga menemukan bahwa pada seni kerajinan rakyat jelata itu terdapat unsur yang penting, yaitu "keindahan dari kesedihan", "keagungan dari kemuraman", semacam ekspresi yang lirih dari tekanan yang berat dalam ketertindasan hidup sehari-hari. Seni keramik “orang-orang biasa” adalah jalan bagi rakyat jelata untuk mengekspresikan dirinya ke dalam keindahan perabotan rumah tangga (yaki dalam bahasa jepang atau ware dalam bahasa Inggris) yang mereka pergunakan sehari-hari. Keindahan karya seni dan fungsi dari perabotan rumah tangga telah menyatu dalam filsafat estetika mingei. Karya seni tidak lagi menjadi milik elit kelas sosial di dalam masyarakat, tetapi diapresiasi oleh semua lapisan masyarakat, dan mencerahkan secara spiritual. Aspek ekspresi individu seniman dan aspek sosial dari karya seni telah menyatu dalam seni keramik gaya mingei. Estetika mingei ini telah memengaruhi empu keramik modern Jepang seperti Shoji Hamada (1894-1978) dan Kawai Kanjiro (1890-1966), hingga seniman keramik kontemporer Jepang seperti Tsukigata Nahiko , Ken Mitsuzuki, dll. Para empu itu, menemukan substansi dari "seni rakyat jelata" sebagai "kesempurnaan dari ketidaksempurnaan" atau wabi-sabi, sebagai kesadaran akan yang sebentar, kerapuhan dari segala sesuatu, keindahan dari yang fana. "Cacat-artistik" itu kemudian dikembangkan sebagai kriteria artistik yang unik oleh empu seni keramik modern Jepang hingga kini. Saat ini seni keramik gaya mingei, bersama dengan filsafat estetikanya, telah berkembang di seluruh dunia bersama gaya seni keramik lainnya dari Jepang seperti gaya bizen, shigaraki, iga, shino, dll. Hampir semua seniman seni keramik kontemporer tak bisa mengabaikan jasa dari estetika mingei sebagai pelopor kebangkitan seni keramik dunia pada awal abad ke-20 hingga saat ini. Bernard Leach di Inggris dan Warren MacKenzie di Amerika Serikat, pelopor kebangkitan seni keramik modern di negaranya, adalah penganut estetika mingei. Keunikan dari seni keramik mingei adalah mampu memberikan landasan filosofis dan spiritual yang kokoh di dalam estetika seni keramik “orang-orang biasa”. Dan itulah kreativitas, sebuah inovasi jenial yang mampu memadukan gaya dan teknik tradisi dengan spirit egaliter dari dunia modern. Jadi, siapa bilang seni "rendah" rakyat jelata itu tidak bisa diangkat menjadi seni kelas dunia seperti seni keramik gaya mingei yang kita kenal saat ini? 3. Kintsugi, Seni dari Keramik yang Retak dan Pecah Cawan retak yang sudah diperbaiki dengan teknik “kintsugi” berlapis emas, Jepang. 18 Orang Jepang itu memang unik dan kreatif dalam menciptakan karya seni. Misal, ketika salah satu karya seni keramik mereka retak atau pecah, mereka berusaha memperbaikinya dengan cara yang artistik sekaligus unik, yang justru mampu menghadirkan keindahan tersendiri. Kintsugi atau kintsukuroi adalah seni Jepang dalam memperbaiki tembikar yang retak atau pecah dengan menggunakan zat perekat yang dilapisi bubuk emas, perak, atau platinum. Filosofi dari seni kintsugi yang telah ada sejak abad ke-15 adalah memperlakukan kerusakan dan membuat perbaikan menjadi bagian dari sejarah objek, bukan sesuatu yang mesti disamarkan atau dihapuskan. Filsafat estetika dari kintsugi memiliki kesamaan dengan filosofi seni keramik Jepang, "wabi-sabi", yaitu menerima cacat atau ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kesempurnaan estetika itu sendiri. Estetika "wabi-sabi" menghargai keausan dan cacat dari objek seni menjadi subjek artistik itu sendiri. Begitu pun halnya dengan kintsugi, cacat akibat keretakan yang tak bisa ditutupi oleh perbaikan diterima sebagai suatu peristiwa dalam kehidupan objek yang tak sempurna. Kintsugi juga berhubungan dengan prinsip spiritual Zen: "tiada pikiran". Yang meliputi konsep ketakterikatan dan penerimaan terhadap kerusakan yang tak tertolak atau duka sebagai aspek alami kehidupan manusia. Meskipun awalnya diabaikan sebagai bentuk seni, kintsugi dan metode perbaikannya kini justru dianggap sebagai bagian dari seni keramik. Beberapa karya kintsugi, dari yang klasik hingga modern, telah pula ditampilkan dalam beberapa pameran di Galeri Smithsonian dan Metropolitan Museum of Art (MoMA) di New York City. "Cacat" itu bukan sesuatu yang mesti ditolak, bahkan justru bisa dihadirkan menjadi satu karya artistik yang mengagumkan. Seni kintsugi telah membuktikannya, dan, hei!, ini cukup "melegakan" ternyata. 4. Bagaimana dengan Seni Kerajinan di Indonesia? Indonesia, termasuk Lampung, memiliki kekayaan artefak budaya yang amat beragam. Mulai dari seni tenun, seni gerabah, peralatan seni musik, seni patung, dll. Lantas mengapa seni kerajinan itu seperti “mati suri” atau jalan di tempat, tak mampu melintasi batas negara seperti seni keramik Jepang? Mulanya seni keramik Jepang juga telah “mati suri” selama dua abad. Pada awal abad ke-20 masyarakat dan pemerintah Jepang tengah sibuk membangun industrinya dan mengabaikan kekayaan budayanya. Hingga sekelompok filsuf dan seniman muda Jepang, yang dipelopori oleh Yanagi Soetsu mulai tergerak untuk menggali spirit, teknik, dan filsafat estetika dari seni kerajinan tradisional Jepang. Semangat itu muncul setelah Yanagi Soetsu membaca hasil penelitian dari Bernard Leach, seorang seniman keramik dari Inggris, terhadap kekayaan seni keramik Jepang. Begitulah muasalnya, konsep filosofis dari Yanagi Soetsu, hasil riset dari Bernard Leach, dan teknik seni keramik dari Shoji Hamada dan Kawai Kanjiro (dua tokoh seniman keramik modern Jepang) bertemu menghasilkan seni keramik gaya mingei dan menginspirasi lahirnya seni keramik modern Jepang dan dunia hingga saat ini. 19 Patung keramik kontemporer berbentuk piring, karya Tom Coleman, Amerika Serikat. Setelah nyaris setengah abad para pelopor seni mingei itu bergulat dan berkarya, akhirnya pemerintah Jepang mulai memerhatikan dan memberi penghargaan secara rutin kepada para pelopor dan inovator dalam seni kerajinan—baik seni keramik, seni tekstil, seni kayu, seni lukisan cukil kayu, dll. pada tahun 1955. Penghargaan itu diberi nama Living National Treasure (LNT). Para pelopor seni mingei juga telah diberikan penghargaan ini oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, pemerintah Jepang juga membuat atau membantu pendirian berbagai museum bagi karya-karya seni kerajinan Jepang. Pemerintah Jepang juga giat mempromosikan karya seni kerajinannya baik melalui media massa, pameran internasional, dukungan bagi seniman luar untuk mengadakan riset tentang seni kerajinan Jepang, dll. Jadi, sukses yang fenomenal dari bangkitnya seni kerajian Jepang, khususnya seni keramik Jepang, adalah hasil sinergi dari semangat inovatif seniman, riset yang mendalam dari ilmuwan, kolaborasi intens dengan seniman mancanegara, apresiasi masyarakat yang baik, dan dukungan kebijakan pemerintah secara kontinyu. Hal itu dikerjakan secara terus-menerus, dengan segala dinamikanya, selama hampir satu abad. Menurut pikiran saya, jika seni kerajinan Indonesia—maupun seni kontemporer atau seni tradisi Indonesia saat ini—mau diapresiasi oleh dunia, menjadi bagian dari kebudayaan dunia, maka mesti belajar dari semangat inovatif kebangkitan seni kerajinan Jepang, khususnya seni keramik Jepang. Semoga. Bandarlampung, 1 Mei 2016 Ahmad Yulden Erwin 20 Riwayat Singkat Penulis Ahmad Yulden Erwin lahir di Tanjungkarang, pada 15 Juli 1972. Ia aktif menulis puisi dan prosa sastra sejak tahun 1987. Tahun 1997, ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Beberapa puisinya pernah diterbitkan di media massa lokal dan nasional, juga dalam beberapa antologi puisi bersama di antaranya: Memetik Puisi Dari Udara (1987), Jung (1994), Daun-Daun Jatuh Tunas-Tunas Tumbuh (1995), Festival Januari (1996), Refleksi Setengah Abad Indonesia (1995), Dari Huma Lada (1996), Mimbar Penyair Abad-21 (1997), Cetik (1999), dll. Setelah tahun 1999 praktis ia berhenti memublikasikan puisi-puisinya dan lebih banyak aktif di gerakan sosial antikorupsi di Komite Anti Korupsi Lampung, sampai saat ini. Pada tahun 1992, ia menjadi juara III dalam Lomba Cipta Puisi Islami “IQRA” tingkat nasional, dengan juri H.B. Jassin. Tahun 1995, ia menjadi juara I dalam Lomba Cipta Puisi pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-III di Jakarta. Selanjutnya, November 2006, puisi-nya yang berjudul ”Hikayat Fansuri” meraih penghargaan 15 besar dalam lomba cipta puisi tingkat nasional oleh Direktorat Kesenian. Tahun 1996 ia diundang Dewan Kesenian Jakarta untuk mengikuti “Mimbar Penyair Abad-21”. Dan tahun 1997 ia kembali diundang Dewan Kesenian Jakarta untuk mengikuti “Pertemuan Sastrawan Nusantara” di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sejak tahun 2012, ia mulai aktif kembali menulis puisi. Pada tahun 2013 beberapa puisinya telah dipublikasikan di beberapa media massa seperti Lampung Post, Kompas Minggu, dan Koran Tempo. Terakhir, Oktober 2013, ia diundang membacakan puisipuisinya dan menjadi narasumber diskusi tentang kritik sastra pada acara Binale Sastra Internasional di Salihara, Jakarta. Tahun 2014 kumpulan puisinya “Perawi Tanpa Rumah” mendapat rekomen-dasi sebagai buku puisi terbaik tahun 2013 oleh majalah Tempo. Pada tahun 2014 narasi puitiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterbitkan di Belanda, bersama dua puluh sastrawan dari berbagai negara di dalam buku “The Empty Place”. Saat ini ia sedang memper-siapkan penerbitan buku “Studi tentang Dua Buah Pir”, kumpulan 400 puisi terjemahan karya lima belas penyair modern dunia dari berbagai negara. 21