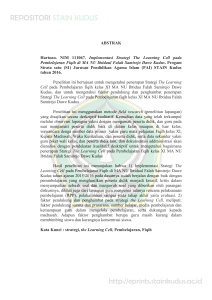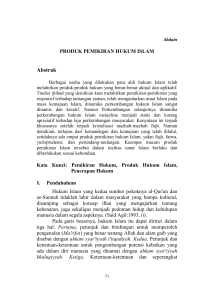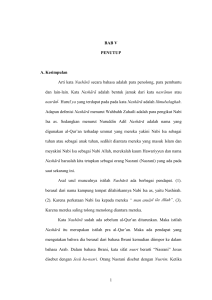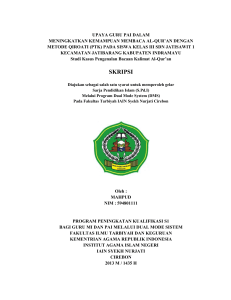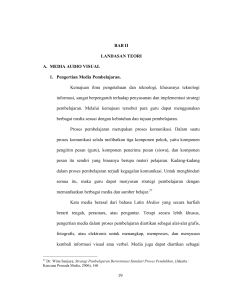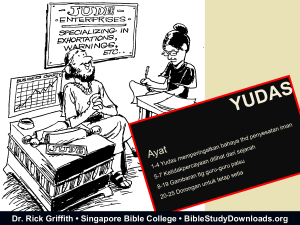Pengembangan Penggunaan Ijtihad dan Aplikasinya
advertisement
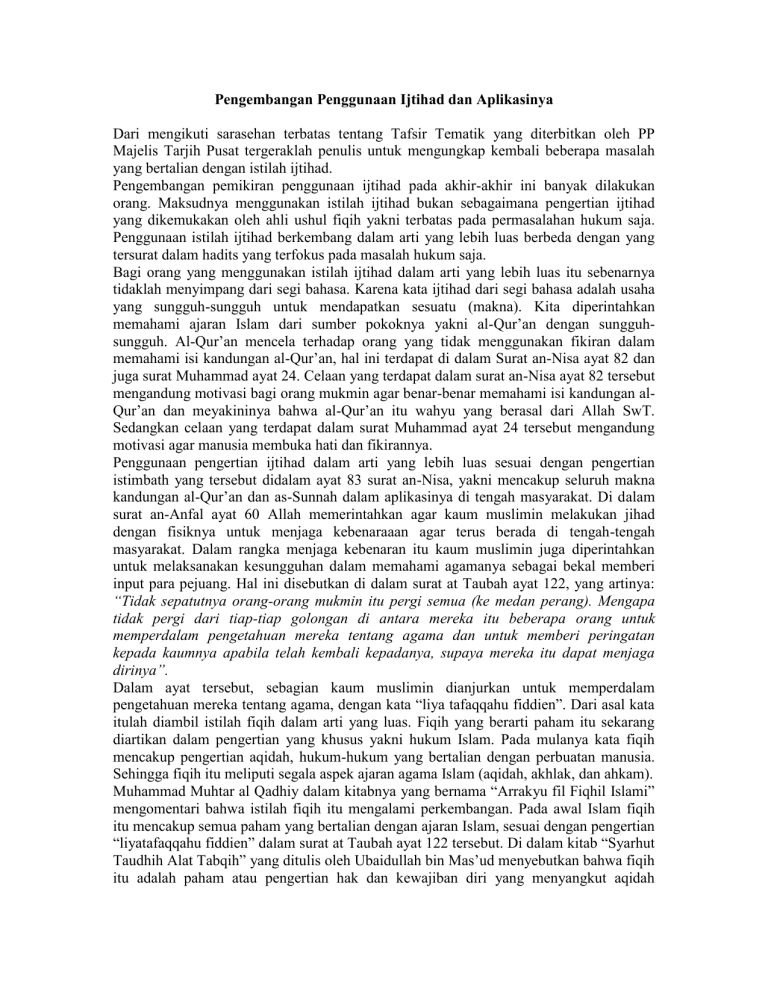
Pengembangan Penggunaan Ijtihad dan Aplikasinya Dari mengikuti sarasehan terbatas tentang Tafsir Tematik yang diterbitkan oleh PP Majelis Tarjih Pusat tergeraklah penulis untuk mengungkap kembali beberapa masalah yang bertalian dengan istilah ijtihad. Pengembangan pemikiran penggunaan ijtihad pada akhir-akhir ini banyak dilakukan orang. Maksudnya menggunakan istilah ijtihad bukan sebagaimana pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqih yakni terbatas pada permasalahan hukum saja. Penggunaan istilah ijtihad berkembang dalam arti yang lebih luas berbeda dengan yang tersurat dalam hadits yang terfokus pada masalah hukum saja. Bagi orang yang menggunakan istilah ijtihad dalam arti yang lebih luas itu sebenarnya tidaklah menyimpang dari segi bahasa. Karena kata ijtihad dari segi bahasa adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu (makna). Kita diperintahkan memahami ajaran Islam dari sumber pokoknya yakni al-Qur’an dengan sungguhsungguh. Al-Qur’an mencela terhadap orang yang tidak menggunakan fikiran dalam memahami isi kandungan al-Qur’an, hal ini terdapat di dalam Surat an-Nisa ayat 82 dan juga surat Muhammad ayat 24. Celaan yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 82 tersebut mengandung motivasi bagi orang mukmin agar benar-benar memahami isi kandungan alQur’an dan meyakininya bahwa al-Qur’an itu wahyu yang berasal dari Allah SwT. Sedangkan celaan yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 24 tersebut mengandung motivasi agar manusia membuka hati dan fikirannya. Penggunaan pengertian ijtihad dalam arti yang lebih luas sesuai dengan pengertian istimbath yang tersebut didalam ayat 83 surat an-Nisa, yakni mencakup seluruh makna kandungan al-Qur’an dan as-Sunnah dalam aplikasinya di tengah masyarakat. Di dalam surat an-Anfal ayat 60 Allah memerintahkan agar kaum muslimin melakukan jihad dengan fisiknya untuk menjaga kebenaraaan agar terus berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka menjaga kebenaran itu kaum muslimin juga diperintahkan untuk melaksanakan kesungguhan dalam memahami agamanya sebagai bekal memberi input para pejuang. Hal ini disebutkan di dalam surat at Taubah ayat 122, yang artinya: “Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. Dalam ayat tersebut, sebagian kaum muslimin dianjurkan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dengan kata “liya tafaqqahu fiddien”. Dari asal kata itulah diambil istilah fiqih dalam arti yang luas. Fiqih yang berarti paham itu sekarang diartikan dalam pengertian yang khusus yakni hukum Islam. Pada mulanya kata fiqih mencakup pengertian aqidah, hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia. Sehingga fiqih itu meliputi segala aspek ajaran agama Islam (aqidah, akhlak, dan ahkam). Muhammad Muhtar al Qadhiy dalam kitabnya yang bernama “Arrakyu fil Fiqhil Islami” mengomentari bahwa istilah fiqih itu mengalami perkembangan. Pada awal Islam fiqih itu mencakup semua paham yang bertalian dengan ajaran Islam, sesuai dengan pengertian “liyatafaqqahu fiddien” dalam surat at Taubah ayat 122 tersebut. Di dalam kitab “Syarhut Taudhih Alat Tabqih” yang ditulis oleh Ubaidullah bin Mas’ud menyebutkan bahwa fiqih itu adalah paham atau pengertian hak dan kewajiban diri yang menyangkut aqidah (seperti wajib beriman), akhlaq seperti kehalusan budi, melakukan perbuatan yang baik dan utama juga kewajiban untuk melakukan ibadah seperti shalat, puasa, jual beli dengan benar dan sebagainya. Ubaidullah mengidentifikasikan pengertian fiqih dalam arti luas. Dan sekarang menggunakan kata ijtihad cenderung dalam pengertian yang lebih luas. Hal ini berarti mengembalikan pengertian makna fiqih kepada makna semula yakni faham agama dan kita dapati penggunaan kata ijtihad untuk mengembangkan pemikiran dan memahami isi kandungan al-Qur’an yang lebih luas. Menurut pendapat saya, pengembangan pemikiran terhadap arti ijtihad ini boleh saja bahkan perlu diteruskan dalam penafsiran al-Qur’an maupun al-Hadits yang belum dituntaskan oleh para ulama pada masa lampau. Dalam penafsiran ayat-ayat kauniyah misalnya seperti penafsiran ayat yang berbunyi “Kunfayakun” dan proses yang disebut sunnatullah dan juga pemahaman terhadap hadits-hadits yang bersifat temporer dan kontekstual. Hal itu perlu dikembangkan pemikirannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang akan lebih mendekatkan kebenaran yang terus dicari oleh manusia. Banyak ayat-ayat yang perlu mendapat penafsiran yang lebih jelas, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula pemikiran tentang hadits yang dapat diartikan temporer seperti hadits Nabi yang berarti “Kami umat yang ummi tidak dapat menulis dan mengerti hisab”. Demikian juga pemikiran hukum amaliyah yang terkenal dengan nama fiqih Islam baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam era globalisasi dan informasi ini sangat memerlukan ijtihad yang bersifat antisipatif, baik dengan cara intiqa’i (selektif) maupun dengan cara insya’i (pemecahan masalah yang baru) seperti telah dipaparkan dalam rubrik ini beberapa waktu yang lampau. Bahkan saya menggarisbawahi adanya pemikiran tentang perlunya perumusan baru mengenai beberapa qaidah dalam masalah ibadah yang pada prinsipnya menunggu dalil, masih berlaku. Namun dalam implementasinya perlu adanya perumusan baru terhadap qaidah dalam ibadah yang bersifat ijtima’iyyah seperti zakat. Dalam perkembangannya ilmu fiqih masa kini telah digelar, seperti fiqhuz zakatnya al Qardlawi. Demikian pula masalah yang bertalian dengan hukum bioteknologi sangat memerlukan tanggapan dan pemikiran yang antisipatif. Persoalan yang perlu dicermati dalam mengartikan ijtihad dalam arti yang lebih luas ialah metodologinya. Apakah disamakan dengan metode penetapan hukum dalam arti sempit ataukah perlu qaidah-qaidah baru, sebagai contoh. Hukum Berijtihad di Kalangan Ulama Persoalan lain yang perlu dibicarakan dalam ijtihad ini adalah hukum berijtihad. Imam Asy Syaukani menukilkan ucapan sebagian ahli fiqih yang artinya: Hendaknya di setiap negara terdapat orang yang mampu berijtihad. Sebab ijtihad itu termasuk fardlu kifayah hukumnya. Imam An Nawawi menyebutkan, bahwa ijtihad mustaqil (yang menggunakan manhajnya sendiri langsung dari dalil syara’) telah terhenti sejak awal abad IV hijrah, sedangkan ijtihad muntasib (yang mendasarkan manhaj sesuatu aliran) masih selalu ada sampai munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Dan ijtihad muntasib ini tidak boleh terputus karena hukumnya fardlu kifayah. Kapan saja penduduk suatu kota mengabaikan ijtihad muntasib ini dan meninggalkannya, maka berdosalah semuanya. Demikian juga menurut pendapat Imam al Mawardi, ar Robbani, al Banawi dan sebagainya. Ibnu Shalah berkata: Pendapat yang saya lihat dari buku-buku para Imam mengisyaratkan bahwa yang dihukumi fardlu kifayah adalah “mujtahid muqayyad” sedangkan pendapat yang kuat menurut saya bahwa yang dihukumi fardlu kifayah adalah ijtihad mutlak. Maksud Ibnu Shalah ialah, untuk melaksanakan fardlu kifayah ini harus ada mujtahid yang mampu menggunakan dalil-dalil syara’ secara langsung. Atas dasar ini, seorang ulama yang telah memiliki dalam dirinya kemampuan untuk berijtihad dan tersedia fasilitas-fasilitas untuk ijtihad hendaknya melengkapi dirinya dengan syarat-syarat ijtihad di bidang ini dan berusaha terus untuk memperluas serta memperdalamnya sehingga ia mencapai derajat ijtihad mutlak. Guna menutup lobang kekosongan dan mengangkat kesulitan dan dosa dari umat Islam, sekarang dilakukan ijtihad jama’i. Ketetapan hukum demikian ini berlaku secara umum dalam segala perbuatan yang hukumnya fardlu kifayah. Bila terdapat seorang yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya hendaknya ada yang maju mengisi kekosongan ini sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada dirinya. Uraian di atas adalah berkenaan dengan hukum ijtihad bila dilihat dari segi deskripsi dan kemampuan. Kalau dilihat dari sudut bermunculannya kejadian yang menuntut adanya fatwa, sebagian ahli ushul membagi tiga yaitu; fardlu ‘ain, fardlu kifayah, dan nadb. Pertama, Ijtihad itu fardlu ‘ain dalam dua keadaan: a. Ijtihad yang harus dilakukan oleh diri seorang mujtahid,, ketika muncul suatu kejadian-kejadian – dengan kata lain, ia harus berijtihad untuk dirinya tentang hal yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, perkawinan, talaknya dan sebagainya. b. Ijtihad dalam suatu perkara yang dimana dia harus memutuskan hukumnya (seperti tiadanya orang selain dirinya sendiri yang bisa dipercaya kefasihan dan kemampuan agamanya. Di saat demikian ini ia wajib berijtihad) bila kebutuhan mendesak cepat untuk menentukan hukum kejadian itu, ia harus cepat pula berijtihad tetapi bila tidak terlalu mendesak, bolehlah ia menundanya. Kedua: Ijtihad yang fardlu kifayah, dalam dua keadaan: a. Bila terjadi suatu perkara pada seseorang lalu minta fatwa kepada seseorang ulama, kewajiban untuk menjawab fatwa itu dipikulkan kepada semua umat, terutama ulama yang diajukan kepadanya pertanyaan itu. Kalau dia atau lainnya menjawab masalah tersebut gugurlah kewajiban atas umat tetapi kalau tidak ada yang menjawab maka berdosalah semuanya. b. Suatu hukum yang harus diputuskan oleh dua orang hakim dalam suatu majelis. Kewajiban untuk memutuskan ini dipikulkan kepada kedua pundak hakim tadi. Bila salah seorang telah menetapkan keputusannya, gugurlah kewajiban atas hakim yang kedua. Ketiga: Hukum Ijtihad yang mandub (bersifat keutamaan), terdapat dalam dua keadaan: a. Ijtihad seorang ulama terhadap perkara yang belum muncul sehingga ia telah mengetahui hukum suatu perkara yang belum terjadi itu. b. Ijtihad terhadap suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang kepadanya sebelum terjadinya perkara itu. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa sebagian ulama menambahkan adanya ijtihad yang haram hukumnya yaitu ijtihad yang bertentangan dengan dalil qath’i sebab ijtihad tersebut dianggap sebagai ijtihad tidak pada tempatnya. Di antara ijtihad yang haram itu adalah ijtihad orang yang tidak berhak melaksanakan ijtihad yaitu ijtihadnya pemimpin yang tidak mempunyai kemampuan, telah diungkapkan oleh hadits bahwa mereka memberi fatwa tanpa didasari ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Macam-macam Ijtihad Masalah lain lagi yang perlu diungkap adalah pelaku ijtihad. Ditinjau dari jumlah pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua yakni: 1. Ijtihad fardi atau ijtihad secara individual yaitu ijtihad dalam sesuatu persoalan hukum yang dilakukan oleh seseorang mujtahid, bukan oleh sekelompok mujtahidin. 2. Ijtihad Jama’i atau ijtihad secara kolektif. Yaitu ijtihad dalam sesuatu persoalan hukum dimana sekelompok mujtahidin mengadakan analisa sesuatu masalah untuk kemudian ditetapkan hukumnya berdasarkan pada dalil dan manhaj yang benar. Ijtihad seperti ini telah dilakukan sejak masa khalifah Abu Bakar, para sahabat telah mengadakan ijtihad Jama’i untuk memerangi orang yang ingkar terhadap Khalifah Abu Bakar, tidak mau membayar zakat, pada hal di masa Nabi mereka membayarnya. Ijtihad semacam ini telah banyak dilakukan oleh sahabat Nabi, para tabi’in di masa lampau. Abu Bakar telah mengadakan ijtihad pengumpulan al-Qur’an, Utsman bin Affan berijtihad jama’i untuk menulis al-Qur’an dalam satu bentuk seragam tulisan. Ijtihad jama’i inilah yang sekarang ditempuh oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan agama Majelis Tarjih memutuskan dalam suatu musyawarah nasional Tarjih yang dulu disebut Muktamar Tarjih. Peserta yang hadir dalam musyawarah nasional ini adalah anggota Lajnah Tarjih dari anggota-anggota Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang ilmu yang berbeda-beda. Ada anggota Lajnah Trajih yang ahli dalam bahasa Arab, ada yang ahli dalam al-Qur’an dan ilmu-ilmunya, ada yang ahli dalam hadits dan ilmu-ilmunya, ada yang ahli dalam ilmu ushul fiqih dan ilmu fiqih. Ada pula yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan. Sumber: Suara Muhammadiyah Edisi 16 2002