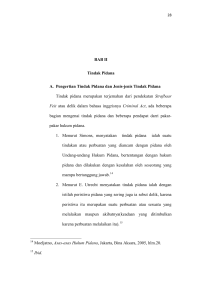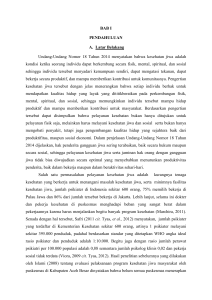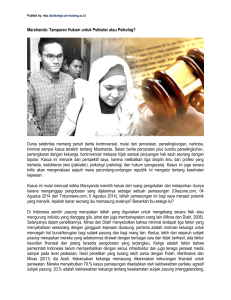jurnal psikiatri indonesia
advertisement

JURNAL PSIKIATRI INDONESIA Vol.1 No.1 Tahun 2016 ISSN: 2502-2512 Bebas Pasung: Ditinjau Dari Aspek Bioetika Kusumadewi A.F 1, Kristanto C.S 2, Sumarni D.W3 1 PPDS Ilmu Kedokteran Jiwa FK UGM 2,3 Staf pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK UGM/ RSUP Dr Sardjito ABSTRAK Bebas pasung merupakan program yang diselenggarakan untuk memperjuangkan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, diantaranya adalah hak untuk dapat hidup secara bebas dan selayaknya manusia. Akan tetapi, orang dengan gangguan jiwa yang dipengaruhi oleh tanda dan gejala gangguan yang dialaminya, berisiko untuk berbuat kekerasan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga berhak untuk dijamin keselamatannya dari ancaman tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan bioetika terhadap kasus bebas pasung yang saling bersinggungan kepentingan tersebut. Kata Kunci: bebas pasung- bioetika Pendahuluan Pemasungan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup lama terjadi. Terdapat sekitar sekitar 20. 000 hingga 30. 000 penderita gangguan jiwa di seluruh Indonesia mendapat perlakuan tidak manusiawi dengan cara dipasung (Purwoko, 2010). Persentase pemasungan antara 0–50 persen bervariasi di antara seluruh provinsi. Metode pemasungan tidak terbatas pada pemasungan secara tradisional dengan menggunakan kayu atau rantai pada kaki, tetapi juga tindakan pengekangan yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung dan penelantaran, yang menyertai salah satu metode pemasungan (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang berani menyatakan program bebas pasung. Program ini telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2010 dan ditargetkan tercapai pada tahun 2019. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menolong orang dengan gangguan jiwa agar mendapat penghargaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pada tahun 2011 Menteri Kesehatan RI sudah mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014. Namun sampai dengan sekarang (tahun 2014) belum terlihat penanganan yang signifikan dan komprehensif dalam penanganan dini penderita gangguan jiwa. Program Indonesia Bebas Pasung 2014 saat ini direvisi menjadi Program Indonesia Bebas Pasung 2019, sehingga Indonesia dalam menentukan ketercapaian target masih ada 5 tahun lagi atau bahkan lebih cepat karena proses ini masih berlangsung berkesinambungan dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten (Yud, 2014). Akan tetapi, berbagai permasalahan baru muncul seperti bagaimana perlindungan terhadap masyarakat paska klien dibebaskan dari pemasungan, bagaimana kehidupan klien paska mendapat pengobatan di rumah sakit jiwa, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pengobatan klien, bagaimana tinjauan secara agama dan budaya mengenai penanganan terhadap klien paska pemasungan. Hal ini mendorong perlunya suatu tinjauan dari aspek bioetika yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis berbagai permasalahan tersebut dan langkah-langkah apa yang sekiranya perlu ditempuh untuk mengatasinya. Evidence Based Practice Indonesia Web: http://ebpi.asia Email: [email protected] Jurnal Psikiatri Indonesia Vol: 1, No:1 Tahun : 2016 Ilustrasi kasus Bapak T, seorang laki-laki berumur 52 tahun, penderita skizofrenia sudah 10 tahun. Ia memiliki riwayat sering menyerang orang lain dan suka mengejar-ngejar perempuan di desanya. Bapak T memiliki 3 orang anak yang semuanya sudah berkeluarga. Istrinya meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Anak-anak merasa kesulitan dalam merawat bapak T. Kebetulan tempat tinggalnya di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan jiwa. Suatu hari bapak T mengamuk dan membakar rumah salah seorang tetangganya. Bapak T menuduh tetangganya inilah yang menyebabkan istrinya meninggal. Bapak T mengancam hendak membunuh tetangganya tersebut. Untungnya berhasil dicegah oleh warga. Anak-anak bapak T akhirnya membuat pasung dari balok kayu di belakang rumahnya. Bapak T dipasung selama 7 tahun dalam keadaan yang menyedihkan hingga akhirnya diketahui oleh petugas puskesmas setempat dan dibebaskan. Bapak T dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 bulan. Sesudah mondok, bapak T akan dipulangkan. Akan tetapi warga menolak karena masih takut kalau-kalau bapak T sewaktu-waktu kumat dan menyerang warga desa. Bapak T menolak di bawa ke panti sosial untuk rehabilitasi karena ingin dekat dengan anak-anaknya dan merasa kalau di panti itu sama saja dengan di buang oleh keluarga. Keluarga tetap memaksa petugas untuk membawa bapak T ke panti dengan alasan tidak sanggup mengurusi lagi dan tidak mau bermasalah dengan warga sekitar. Bapak T juga menolak kontrol ke rumah sakit dengan alasan dirinya sudah sembuh. Pembahasan Pemasungan adalah suatu tindakan pembatasan gerak seseorang yang mengalami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara pengekangan fisik dalam jangka waktu yang tidak tertentu yang menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi orang tersebut. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan, tahun 2010 ada 383 kasus pasung di Indonesia, meningkat menjadi 1.139 kasus di tahun 2011 dan sebanyak 803 di tahun 2012. Bahkan dilaporkan sebanyak 57.000 ISSN: 2502-2512 Hal.22 orang dengan gangguan jiwa berat pernah dipasung (http:///www.depkes.go.id/). Ditinjau dari aspek hak asasi manusia, pemasungan termasuk bentuk pelanggaran terhadap martabat sebagai manusia karena membatasi kebebasan dan kemerdekaannya. Pemasungan juga merupakan bentuk pengabaian, penelantaran, pengucilan terhadap manusia yang masih hidup sehingga mengakibatkan penderitaan. Sebagaimana disebutkan dalam deklarasi WHO bahwa orang dengan gangguan jiwa pun masih berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk kemerdekaan. Secara hukum nasional, penderita dengan gangguan jiwa selayaknya tidak dipasung melainkan berhak mendapatkan perawatan rehabilitasi atau penyembuhan yang pembiayaannya dibantu oleh negara. Hal ini sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Juga tertuang dalam UUD Negara Indonesia pasal 28G ayat 2 yang berbunyi ”Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Ketentuan pasal 28G ayat 2 menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit baik fisik maupun psikis. Pasal 28 ayat 1 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pada tahun 2011, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program Indonesia Bebas Pasung pada tahun 2014. Namun, karena beberapa kendala, program ini direvisi menjadi Program Indonesia Bebas Pasung 2019. Program ini tidak berhenti hingga penderita dibebaskan, tetapi membutuhkan pendampingan yang terus menerus sampai pasien benar-benar sembuh dan bisa bersosialisi dengan orang lain secara normal. Ketiadaan akses yang berkesinambungan antara rumah sakit dan komunitas menyebabkan keluarga Jurnal Psikiatri Indonesia Vol: 1, No:1 Tahun : 2016 kembali mendapat beban yang paling besar. Setelah dari rumah sakit, penderita kontrol sekali dua kali ke psikiater. Selepas itu kembali ditangani oleh keluarganya yang sering belum cukup pengetahuan untuk mendukung proses pemulihan. Penderita tetap diisolasi secara sosial, tidak diberi kesempatan kerja maupun bersosialisasi karena masih takutnya warga bila sewaktu-waktu penderita mengalami kekambuhan. Pada ilustrasi kasus di atas, tampak bahwa masyarakat maupun keluarga belum siap untuk menerima kembali penderita karena masih takut bila penderita mengalami kekambuhan dan membahayakan orang lain. Kesulitan juga muncul karena bapak T tidak mau minum obat. Dilema etik yang muncul pada kasus di atas antara lain sebagai berikut: 1. Apakah Bapak T sudah siap dikembalikan ke masyarakat bila dirinya tidak mau minum obat? 2. Apakah dapat dibenarkan bila keluarga atau petugas memaksa bapak T untuk kembali berobat ke rumah sakit? 3. Apakah dapat dibenarkan bila bapak T dipaksa untuk tinggal di panti sosial dengan alasan keamanan? 4. Bagaimana memberikan edukasi yang tepat untuk keluarga dan masyarakat menghadapi kasus bapak T seperti di atas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat menggunakan kaidah-kaidah bioetika . Bioetika, menurut Samuel Gorovitz pada tahun 1995, adalah suatu penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Bioetika juga diartikan sebagai studi tentang isu-isu etika dan membuat keputusan yang dihubungkan dengan kegunaan kehidupan makhluk hidup dan obatobatan termasuk di dalamnya etika kedokteran dan etika lingkungan. Dengan demikian, bioetika terkait dengan kegiatan yang mencari jawab dan menawarkan pemecahan masalah dari konflik moral yang dapat diterima secara lebih komprehensif (Taher, 2003). Bioetika mengacu pada 4 nilai dasar yaitu otonomi, beneficence, nonmaleficence, justice. Pada kasus di atas, muncul berbagai nilai-nilai yang harus dipertimbangkan antara ISSN: 2502-2512 Hal.23 lain nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etika, nilai-nilai keadilan, serta nilai-nilai profesionalisme petugas kesehatan. Bapak T adalah seorang manusia yang perlu dihargai nilai-nilai kemanusiaannya. Walaupun bapak T adalah penderita gangguan jiwa, bapak T juga memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk menolak pengobatan. Akan tetapi, bapak T tidak merasa dirinya sakit. Walaupun gejala sudah membaik dan sudah dipulangkan dari rumah sakit, namun bapak T masih belum memiliki tilikan diri yang sepenuhnya. Artinya sejauhmana pasien menyadari dirinya sakit dan berbuat sesuatu untuk melakukan pengobatan. Seharusnya ketika hendak dipulangkan dari rumah sakit, pasien sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 1. Tidak membahayakan diri dan orang lain 2. Paham obat yang diberikan dokter dan bersedia untuk kontrol secara rutin 3. Mampu bersosialisasi dengan orang lain 4. Mampu mengisi waktu luang 5. Mampu mengendalikan diri 6. Aktivitas dasar harian mampu dikerjakan secara mandiri 7. Mampu menunjukkan kemampuan diri. Rumah sakit tentunya memiliki standar operasional prosedur untuk memulangkan pasiennya. Permasalahannya, seringkali dibatasi oleh pembiayaan asuransi yang menentukan bahwa maksimal pasien rawat inap adalah 30 hari. Seharusnya ada mekanisme khusus/ perkecualian untuk pasien yang memiliki riwayat tindakan berbahaya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang lebih lama dibandingkan dengan pasien yang tidak memiliki riwayat tindakan kekerasan sebelumnya. Untuk menilai besarnya potensi risiko berbuat kekerasan dimasyarakat dapat menggunakan instrumen yang sudah divalidasi di rumah sakit. Ditinjau dari aspek yuridis, orang seperti bapak T tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan karena gangguan mental dan gangguan tilikan diri. Pasien yang berkompeten menurut peraturan perundangundangan di Indonesia adalah pasien dewasa atau bukan anak atau telah/ pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami retardasi mental atau penyakit mental sehingga Jurnal Psikiatri Indonesia Vol: 1, No:1 Tahun : 2016 mampu membuat keputusan secara bebas. Apabila pasien tidak berkompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat dengan urutan sebagai berikut: 1)suami atau istri; 2) ayah atau ibu; 3) anak kandung; 4) saudara kandung;5) wali. Hal ini dituangkan jelas dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Menurut undang-undang Berdasarkan ketentuan pasal 22 dalam hal orang dengan gangguan jiwa yang menunjukkan pikiran dan atau perilaku yang membahayakan dirinya dan orang lain atau sekitarnya , maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofarmakan terhadap ODGJ sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya. Jadi dalam hal ini, keluarga berhak untuk mengambil keputusan untuk pasien terkait dengan pengobatannya. Di dalam etika kedokteran terdapat prinsip otonomi, dimana pasien berhak atas dirinya sendiri. Konsep otonomi hanyalah salah satu dari banyak pertimbangan etik sehingga penghormatan terhadap prinsip otonomi tidak boleh melebihi nilai-nilai moral lainnya. Selain itu, konsep otonomis endiri lebih luas dan bersifat relatif. Pada kasus ancaman kekerasan bapak T, otonomi disini dapat diperkecualikan. Hal ini karena kapasitas mental bapak T tidak bisa dikatakan layak untuk mengambil keputusan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip beneficence. Prinsip beneficence adalah tanggung jawab untuk melakukan kebaikan yang menguntungkan pasien dan menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan pasien. Ciri dari nilai ini adalah mengutamakan kebaikan atau manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Ketika bapak T tidak mau minum obat, maka bapak T berisiko mengalami kekambuhan / relaps. Pada saat bapak T relaps, risiko mengancam keselamatan warga masih cukup besar. Dengan demikian dapat dibenarkan tindakan memaksa bapak T untuk berobat ke rumah sakit supaya gejalanya dapat dikontrol di kemudian hari. Alternatif lainnya adalah dibawa ke panti untuk sementara waktu hingga pasien benar-benar bisa minum obat sendiri. Selain itu juga dapat ISSN: 2502-2512 Hal.24 memberdayakan fasilitas home care yaitu pemberian obat injeksi jangka panjang yang diberikan oleh petugas kesehatan tiap bulan sekali. Dalam hal ini manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Prinsip berikutnya adalah nilai nonmaleficence. Petugas dalam memberikan intervensi tidak boleh merugikan pasien. Dalam artian obat-obat diberikan memang sesuai dengan indikasi dan efek samping yang wajar. Prinsip selanjutnya adalah justice. Inti dari prinsip keadilan adalah berlaku adil pada setiap pasien. Jadi walaupun bapak T penderita gangguan jiwa, bapak T wajib diperlakukan sama seperti pasien pasien yang lainnya. Petugas kesehatan dan keluarga tetap harus menghargai hak hukum dari pasien. Bapak T sebagai manusia berhak mendapat perlindungan hukum. Ditinjau dari konsep martabat manusia (human dignity) sering digunakan sebagai argumen untuk menentang pemasungan. Setidaknya ada dua konsep martabat yaitu: 1. Martabat inherent atau yang melekat yang berarti kualitas moral universal yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dicabut. 2. Martabat individualistis yaitu martabat yang terkait dengan tujuan pribadi dan keadaan sosial yang dapat ditingkatkan. Pemasungan secara etik memang melanggar martabat manusia baik martabat inherent maupun martabat individual. Hal ini dikarenakan pemasungan merupakan hambatan dalam intergritas kebebasan seseorang. Akan tetapi, bila dimasukkan ke panti rehabilitasi selama dilakukan oleh staf-staf yang berkompeten dan tetap diperlakukan dengan hormat, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran martabat, tetapi justru untuk mempertahankan martabatnya dari rasa malu karena dikucilkan masyarakat. Jadi indikasi untuk memasukkan ke panti rehabilitasi pada kasus bapak T di atas adalah: 1. Untuk mencegah bahaya yang akan terjadi kepada pasien atau orang lain 2. Untuk mencegah gangguan serius dari program pengobatan atau kerusakan yang signifikan pada lingkungan fisik Jurnal Psikiatri Indonesia Vol: 1, No:1 Tahun : 2016 3. 4. Untuk membantu pengobatan sebagai bagian dari terapi komprehensif terhadap orang dengan gangguan jiwa Untuk menurunkan stimulasi/ rangsangan negatif yang mungkin diterima pasien bila dibebaskan di masyarakat misalnya ejekan, hinaan, tudingan dan sebagainya. Dengan dimasukkannya bapak T ke panti rehabilitasi, diharapkan akan memberikan pengalaman positif bagi pasien, memberikan latihan dalam mengendalikan halusinasi, latihan pengendalian emosi juga latihan keterampilan yang diharapkan memperkuat bekal pasien agar nantinya lebih siap dikembalikan ke masyarakat dan meminimalkan gesekan konflik-konflik yang kemungkinan terjadi. Kesimpulan Pendekatan bioetika diperlukan untuk membuat manajemen suatu masalah secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi profesional medis, melainkan juga dari sisi kemanusiaan, setika, hukum, dan sosial. Berbagai dilema etik yang muncul dapat dicari pemecahannya dengan cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan bioetika pada kasus bebas pasung sangat bermanfaat untuk meminimalkan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan konsep pertimbangan yang menyeluruh, diharapkan setiap keputusan yang diambil untuk pasien merupakan keputusan yang paling rasional dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara etik, profesional medik, maupun secara ISSN: 2502-2512 Hal.25 hukum. Pada ilustrasi kasus di atas dapat dibuat ethical statement berikut ini: “Apabila ada orang dengan gangguan jiwa yang mengancam keselamatan diri dan lingkungannya dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis yang adekuat, serta menolak pengobatan, maka dapat dilakukan tindakan pemindahan atas permintaan keluarga dan masyarakat untuk sementara waktu dan menjalani pengobatan hingga terjadi perbaikan gejala dan perbaikan insight sepenuhnya”. DAFTAR PUSTAKA Yankouski,B. Masserelli, T. Lee, S. 2012. Ethical Issues Regarding the Use of Restraint and Seclusion in Schools. The School Psychologist Journal. America. Pui, C. 2015. Coercion in Psychiatry-Is Seclusion Ethical?. Medical Students Journal of Australia. Volume 4 Issue 2. Petrini, C. 2013. Ethical Considerations for Evaluating the Issue of Physical Restraint in Psychiatry. Ann Ist Super Sanita. Volume 49.No 3:281-285 Newton, G. Howes. 2013. Use of Seclusion for Managing Behavioural Disturbance in Patients.Advances in Psychiatry Treatment. Volume 19, 422-428