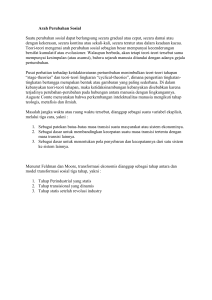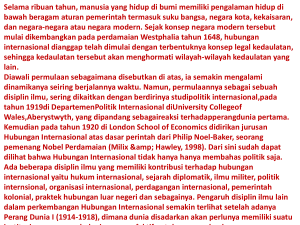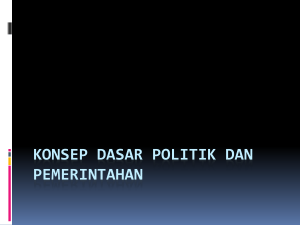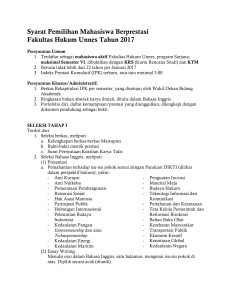Keadilan Transisional
advertisement

Keadilan Transisional Sebuah Tinjauan Komprehensif Ruti G. Teitel Elsam 2004 Keadilan Transisional, Sebuah Tinjauan Analitis-Komprehensif oleh Ruti G. Teitel (Diterjemahkan dari Transitional Justice, Oxford dan New York: Oxford University Press, 2000). Penerjemah Tim Penerjemah Elsam Editor I/Penyelaras Terjemahan Eddie Riyadi Terre Editor II/Penyelaras Bahasa Erasmus Cahyadi T. Desain Sampul: Layout: Cetakan Pertama, Oktober 2004 Hak terjemahan dalam bahasa Indonesia ada pada ELSAM Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. This publication has been produced with the assitance of the European Union. The contents of this publication is the sole responsibility of ELSAM and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. Penerbit ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 Tlp.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519 E-mail: [email protected], [email protected]; Web-site: www.elsam.or.id Prakata Seri Setelah lebih dari 32 tahun hidup di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dengan dukungan ideologi militerisme yang menindas, dan kembali memasuki era keterbukaan, reformasi dan demokrasi, bangsa Indonesia sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Bahkan perbincangan sistematis tentang upaya-upaya penyelesaian hukum dan politis belum menjadi agenda utama banyak kalangan, baik DPR maupun pemerintah. Kalaupun ada, orang cenderung bersikap pragmatis dan seadanya, sehingga mengabaikan prosedur dan sasaran yang sesungguhnya. Kita pun belum memiliki perangkat yang memadai untuk menangani berbagai dampak traumatik dari akibat pelanggaran HAM masa lalu. Sementara di sisi lain, dampak traumatik tersebut semakin kelihatan seperti dalam munculnya aksi-aksi kekerasan masyarakat, resistensi ataupun ketidakpatuhan (social disobedience), atau bahkan melalui keinginan dan upaya untuk melepaskan diri dari negara RI Salah satu masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu secara tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahasan mengenai penyelesaian pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu seyogianya berada di dalam bingkai wacana “transitional justice” karena momentum awal wacana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut adalah pergantian rezim dari rezim Orde Baru yang otoriter menuju rezim baru yang lebih demokratis. Lalu, apa sebenarnya transitional justice? Pertanyaan ini penting karena wacana transitional justice lebih luas daripada “sekadar” penyelesaian kasus demi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Landasan moralnya adalah pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis, tanpa kekerasan, dan mengacu ke tertib hukum, sehingga menjamin peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan. Persoalannya adalah, apa dan bagaimana sikap kita terhadap tindakan pelanggaran HAM masa lalu tersebut? Apakah dengan menghukum atau memaafkan? Apakah yang harus dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Bagaimana dampaknya bila tidak terselesaikan? Bagaimana nasib para korban? Dan bagaimana kita dapat menjamin untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM yang sama pada masa depan? Banyaknya pertanyaan yang harus kita jawab bersama itulah yang menggugah kami, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menerbitkan buku seri transitional justice ini. Selama ini, debat wacana tentang masalah keadilan pada masa transisi selalu mengacu pada literatur negara lain yang nota bene terbatas penggunaannya sebagai bahan komparasi semata. Perkembangan literatur dan bahan bacaan tentang transitional justice dengan konteks Indonesia untuk keperluan konsumsi umum memang masih sangat terbatas. Untuk itulah, seri ini hadir. Untuk mengisi ruang kosong dalam wacana kajian umum tentang “bagaimana kita sebaiknya menyikapi masa lalu” yang selama ini seolah-olah terpinggirkan. Kiranya perlu dicatat bahwa berbagai tawaran dalam seri kali ini bukanlah dimaksudkan sebagai semacam pedoman penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu. Seri ini diterbitkan dengan maksud untuk mengajak kita semua menyadari bahwa ada persoalan mendasar dan mendesak yang harus kita benahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Mendasar, karena menyangkut harkat dan martabat manusia – yang menjadi korban kekerasan dan pelaku kekerasan itu sendiri. Mendesak, karena yang dipertaruhkan adalah pelurusan sejarah, eksistensi kekinian manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama adalah masalah kemanusiaan yang secara prinsip merupakan masalah universal, bukan melulu menjadi masalah kajian satu bidang ilmu tertentu. Itulah mengapa, kendatipun semua uraiannya menukik pada satu tema yang sama, namun pendekatan yang ditawarkan dalam seri ini sangat multidimensional dengan karakter komprehensionalitas bahasan yang cukup kental. Sekaligus hal ini menggambarkan bahwa betapa sangat rumitnya kekerasan masa lalu itu baik pada tataran teoritis maupun praktis. Tidak kurang di sini ada pendekatan filosofis yang mencoba menelusup jauh ke dalam wilayah kelam kekerasan itu. Ia mempertanyakan berbagai ide dasar, gagasan, konsep, keyakinan yang menjadi pembungkus wajah keras masa lalu itu, termasuk mempertanyakan pertanyaan tentang kekerasan itu sendiri. Ada pula pendekatan historis yang menawarkan penjelajahan ruang dan waktu dengan menampilkan berbagai pengalaman negeri lain dalam penyelesaian tindak kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Selain itu, ada pula yang membedahnya dengan pisau analitis – sebab bagaimanapun, karakter kekerasan itu sendiri sangat beragam – namun tetap dalam bingkai komprehensif. Itulah beberapa di antara berbagai pendekatan yang ditawarkan dalam seri ini. Akhirnya, selamat membaca. Pengantar Proyek pembuatan buku ini diinspirasikan oleh gelombang pasang liberalisasi pada penghujung abad kedua-puluh. Pada awal 1980-an, sebuah perdebatan mengemuka berkenaan dengan implikasi “keadilan transisional” terhadap prospek liberalisasi negaranegara. Pertanyaan soal “penghukuman atau impunitas”, apakah ada kewajiban untuk menghukum dalam transisi demokratik, merupakan subjek dari sebuah pertemuan tentang pengambilan kebijakan yang diselenggarakan pada tahun 1990 di Dewan Hubungan Internasional di New York; dalam forum itulah saya diundang dan didaulat untuk menyiapkan tulisan yang bermuatan soal dasar dan latar belakang dilangsungkannya diskusi seperti itu.1 Pada waktu itu, saya menyimpulkan bahwa, bertentangan dengan argumen moral soal penghukuman dalam alternatif-alternatif yang abstrak, alternatif yang beragam untuk menghukum bisa mengungkapkan pesan normatif dari transformasi politik dan aturan hukum, dengan tujuan melanggengkan demokrasi. Dengan bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin, pertanyaan soal keadilan transisional mendapatkan nilai urgensitasnya yang lebih tinggi lagi. Beberapa dari kami yang telah ikut serta dalam perdebatan tentang transisi di negara-negara Amerika Latin berpartisipasi dalam perdebatan yang dilangsungkan di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Di sana, perdebatan tentang penghukuman meluas hingga mencakupi implikasi dari aksi-aksi penyapuan dekomunisasi yang seolah mewabah di rentangan wilayah tersebut. Pada tahun 1992, saya menerima bantuan dana dari Institut Perdamaian Amerika Serikat (U.S. Institute of Peace) untuk memulai proyek komparatif ini dan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah-pemerintah tentang isu keadilan di masa transisi ini. Keikutsertaan saya dalam beberapa konferensi di wilayah-wilayah tersebut membantu membentuk isu ini secara lebih tegas: “Political Justice and Transition to the Rule of Law in East Central Europe”, yang disponsori oleh University of Chicago dan oleh Central European University di Prague pada tahun 1991, dan Konferensi Salzburg yang bertajuk “Justice in Times of Transition” pada tahun 1992, yang diselenggarakan oleh Foundation for a Civil Society. Pada tahun 1993, dalam sebuah konferensi, “Restitution in Eastern Europe”, yang diselenggarakan oleh Central European University, saya mengemukakan gagasan yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam sebuah bab tentang keadilan reparatoris dalam buku ini. Pemikiran saya tentang peran penyelidikan historis dibentuk oleh sebuah konferensi yang saya sendiri turut membantu mengorganisirnya di Central European University, Budapest, pada musim gugur tahun 1992, dan dielaborasi dalam sebuah makalah yang dibawakan pada 1 Lihat Ruti Teitel, “How Are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” (makalah yang disiapkan untuk Council on Foreign Relations New York, N.Y., 17 Mei, 1990). 1 sebuah konferensi yang diselenggarakan pada tahun 1994 di Yale Law School dengan tajuk “Delibarative Democracy and Human Rights”. Aspek-aspek komparatif lebih lanjut dieksplorasi pada Seventeenth Annual German Studies Association, di mana saya membawakan makalah berjudul “Justice in Transition in Unified Germany”. Studi tentang preseden-preseden pasca-perang dipersubur dalam sejumlah simposia yang saya juga turut bantu dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun di Boston College Law School, dengan dukungan dari Holocaust-Human Rights Research Project, termasuk juga di New York Law School. Saya menghabiskan kesempatan melakukan penelitian saya sebagai Senior Schell Fellow di Yale Law School, di mana saya membawakan sebuah seminar tentang buku ini dan menarik manfaat dari berbagai diskusi baik di dalam maupun di luar kelas. Beragam porsi buku ini telah dipresentasikan pada Lokakarya Fakultas Yale Law School, termasuk juga lokakarya di Boston College Law School, Cardozo Law School, Columbia University Law School, University of Connecticut Law School, Cornell Law School, New York Law School, dan University of Michigan Law School. Bagian dalam bab kesimpulan dipresentasikan pada Lokakarya New York University Political Theory. Bagian-bagian yang menguraikan bab tentang keadilan konstitusional telah didiskusikan pada Georgetown University Law School Biennial Constitutional Law Discussion Group (1995). Pada pertemuan The American Philosophical Association’s Eastern Division (1996), saya menjadi partisipan dalam sebuah diskusi panel bertema “Justice, Amnesties, and Truth-Tellings.” Beberapa isu dalam bab tentang peradilan pidana telah dipresentasikan dalam sebuah kuliah khusus di mana saya secara khusus pula diundang untuk memberikan kuliah tersebut di University of Frankfurt (Januari 1998). Bagianbagian berisikan bab tentang keadilan kriminal yang berkenaan dengan Eropa Timur dipresentasikan pada pertemuan tahunan The American Association of International Law (April 1998). Bagian-bagian yang menyangkut keadilan kriminal dan kebaikan budi untuk mengampuni (clemency) dipresentasikan pada sebuah lokakarya di University of Edinburgh (Juni 1998). Banyak rekan dan sahabat telah memberikan bantuannya dalam bentuk komentar yang berharga, nasihat, dan dorongan dalam proses penggarapan proyek ini. Pertama, terima kasihku untuk para editor saya di Oxford. Saya berhutang budi kepada Jack Balkin, Robert Burt, Paul Dubinsky, Stephen Ellmann, Owen Fiss, John Ferejohn, George Fletcher, Richard Friedman, Ryan Goodman, Robert Gordon, Derek Jinks, Paul Kahn, Harold Koh, Bill Lapiana, Larry Lessig, Klaus Lüderssen, Tim Lytton, Jack Rakove, Andrzej Rapacynski, Michel Rosenfeld, András Sajó, Marcelo Sancinetti, Peter Schuck, Tony Sebok, Richard Sherwin, Suzanne Stone, Ariel Teitel, dan dua pengamat anonim. Ucapan terima kasih yang khusus saya tujukan kepada Zoe Hilden dan Jonathan Stein atas nasihat mereka yang sangat membantu banyak dan atas masukan-masukan mereka di bidang editorial. Saya paling berhutang budi atas dukungan dari Dekan Harry Wallington di institusi saya sendiri, New York Law School, dan Dekan Anthony Kronman di Yale Law School. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada sejumlah hakim pengadilan konstitusional atas keikhlasannya dalam memberikan kontribusi terhadap riset saya ini, yaitu: Vojtech Cepl, Lech Garlicki, Dieter Grimm, Richard Goldstone, dan Laszlo Solyum. Saya menghaturkan terima kasih kepada para mahasiswa 2 hak asasi manusia dalam rezim-rezim transisional di New York dan Yale Law School atas diskusi dengan mereka yang sangat membantu terhadap berbagai gagasan dalam buku ini. Saya berhutang budi kepada Camille Broussard dari Perpustakaan New York Law School dan kepada asisten periset di New York dan Yale Law School, termasuk Dana Wolpert, Sabrina Bagdasarian, Federica Bisone, Jayni Edelstein, Jonathan Holub, Jessica LaMarche, Karen Owen, dan Naveen Rahman, atas bantuan mereka semua dalam penelitian untuk buku ini. Untuk sumbangannya dalam proses penelitian untuk penulisan buku ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Neil Kritz dari U.S. Institute of Peace, Dwight Semler dan Ania Budziak dari Center for Constitutionalismin East Europe di University of Chicago, Holly Cartner of Human Rights Watch, Robert Weiner dari Lawyers Committee for Human Rights dan Ariel Dulitsky dari Center for Justice and International Law. Saya juga sangat berterima kasih kepada Brenda Davis Lebron untuk bantuan wordprocessing yang diberikannya dan kepada Belinda Cooper dan Leszek Mitrus atas bantuan penerjemahannya. Dukungan keuangan untuk penelitian buku ini disediakan oleh Ernst Stiefel Fund di New York Law School, proyek bantuan dari U.S. Intitute of Peace yang disediakan untuk jangka waktu 1992-1993 dan oleh The Orville H. Schell, Jr., Center for International Human Rights di Yale Law School untuk tahun 1995 dan tahun 1996. Terakhir, saya merasa berutang banyak sekali kepada almarhum Owen M. Kupferschmid. Berbagai percakapan kami yang berkisar seputar masalah keadilan pasca-perang dan dorongannya yang penuh cinta kasih telah menjadi inspirasi bagi saya untuk memulai proyek ini. Berhubung buku ini ditulis dalam tahun-tahun belakangan ini, maka ia juga menjangkau serta menekankan kembali kejadian-kejadian yang membuat kita menahan dan kemudian menarik nafas panjang di penghujung abad kedua-puluh. Namun, kendatipun tulisan ini kita selesaikan, transisi terus saja berlangsung; sebagai contoh, transisi Afrika Selatan keluar dari rezim apartheid tetap berjalan, dan ada juga temuantemuan penting dan kemajuan-kemajuan signifikan di Irlandia Utara dan di berbagai tempat di berbagai belahan dunia ini. Perkembangan ini kemudian berdampak pada tak terhindarkannya ketidaksempurnaan dari buku ini. Perkembangan-perkembangan tersebut juga menguatkan relevansi dan vitalitas subjek pembahasan buku ini, dan pada saat yang sama juga memperlihatkan sekaligus ketidakcukupannya dan kemungkinannya untuk dijadikan sumber inspirasi bagi upaya-upaya selanjutnya. New York City Desember 1999. R. G. T. 3 Daftar Isi Prakata Seri Pengantar Daftar Isi Pendahuluan 1. Kedaulatan Hukum dalam Transisi • Dilema Kedaulatan Hukum: Transisi Pasca-Perang • Pergeseran Gambaran Legalitas: Transisi Pasca-Komunis • Konstruksi Transisional tentang Legalitas • Badan Pengadilan Transisional • Praktik Ajudikatif Transformatif: Beberapa Kesimpulan 2. Peradilan Pidana • Dasar Argumen Peradilan Pidana dalam Masa Transisi • Dilema Transisional dan Pergeseran Paradigma Nuremberg • Penerapan Preseden Nuremberg di Pengadilan Nasional • Keadilan Transisional dan Tatanan Hukum Nasional dalam Perspektif Komparatif • Sanksi Pidana Terbatas • Peradilan Pidana Terbatas dan Konstruksi Transisi • Amnesti Transisional • Batasan Pengampunan di Negara Liberal: Kejahatan terhadap Kemanusiaan • Paradoks Jangka Waktu • Peradilan Pidana Transisional: Beberapa Kesimpulan 3. Keadilan Historis • Sejarah Hukum: Keadilan Historis dan Pengadilan Pidana • Dilema Keadilan Politis • Penghilangan dan Repesentasi • Kebenaran yang Diciptakan: Epistemologi Kebenaran Resmi • Politik Ingatan: Mengaitkan Rezim Sejarah dan Rezim Politik • Kebenaran atau Keadilan: Kebenaran sebagai Pendahulu Keadilan? • Keadilan Historis setelah Totalitarianisme • Keadilan Historis dalam Bayang-Bayang Komunisme • Kebebasan Informasi: Menegaskan Akses di Masa Depan • Hukum Sejarah • “Perdebatan Sejarawan”: Menarik Garis Pembatas Masa Lalu • Memelihara Keadilan Historis Melalui Hukum 1 • • • “Keadilan Puitik”: Narasi Transisi Tentang Penyeberangan Sungai dan Laut, tentang Pembuangan dan Kepulangan Keadilan Historis Transisional: Beberapa Kesimpulan 4. Keadilan Raparatoris • Reparasi dalam Alkitab: Keluaran (Eksodus) dari Mesir • Reparasi Pasca-Perang dan Kesalahan Perang Keseluruhan • Wiedergutmachung dan Schilumim • Perang Kotor, Penghilangan dan Rekonsiliasi: Peran Reparasi • Reparasi dan Privatisasi setelah Komunisme • Dilema Keadilan Reparatoris Transisional dan Kedaulatan Hukum • Penundaan Keadilan Reparatoris: Dilema Perjalanan Waktu • Persistensi Keadilan Reparatoris yang Belum Terselesaikan dan Politik Kontemporer: Dilema “Affirmative Action” • Dilema Transitory Tort • Keadilan Reparatoris Transisional 5. Keadilan Administratif • Sodom dan Gomora: “Pembersihan” Dua Kota yang Jahat • Merekonstruksi Amerika • Pembebasan Melalui Hukum • Epuracion dan Zuivering: Politik Penyingkiran • Lustrace dan Bereinigung: Pembersihan Politik di Eropa Tengah dan Timur • Demiliterisasi terhadap Negara Kemanan Nasional • Demokrasi Militan • Partai dan Rakyat • Demokrasi Militan dan Negara Liberal • Keadilan antar-Generasi • Keadilan Administratif Transisional 6. Keadilan Konstitusional • Model-Model Utama • Pergeseran dari Pemerintahan Otoriter • Keadilan Konstitusional sang Pemenang • Revolusi Damai dan Konstitusinya • Konstitusi Amerika: Tinjauan Transisional • Konstitusionalisme Transisional: Beberapa Kesimpulan 7. Menuju Teori Keadilan Transisional • Keadilan Transisional dan Jurisprudensi Transisional: Sebuah Paradigma • Konstruktivisme Transisional 2 • • Sebuah Teori tentang Keadilan Transisional Keadilan Transisional dan Identitas Liberal Epilog Catatan Daftar Pustaka Indeks 3 Pendahuluan Dalam dekade belakangan ini, masyarakat di seluruh penjuru dunia – Amerika Latin, Eropa Timur, bekas Uni Soviet, Afrika – berhasil menjatuhkan kediktatoran militer dan rezim totaliter, dan menggantikannya dengan pemerintahan yang mengedepankan kebebasan dan demokrasi. Pada masa-masa gerakan politik berskala besar untuk meninggalkan pemerintahan non-liberal ini, timbul satu pertanyaan yang penting. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi masa lalu mereka yang kelam? Pertanyaan ini mengarah ke pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan hubungan sikap terhadap masa lalu negara dengan masa depannya. Bagaimana tercipta pemahaman sosial terhadap rezim baru yang berkomitmen pada “kedaulatan hukum”? [Di sini ditawarkan penerjemahan rule of law dengan “kedaulatan hukum” ketimbang “aturan hukum” atau “kepastian hukum”; “kedaulatan hukum” lebih mewakili apa yang dimaksudkan oleh istilah itu dalam bahasa Inggrisnya, ed.] Keputusankeputusan legal mana sajakah yang memiliki signifikansi dalam perubahan? Apa saja, andaikan ada, hubungan antara respon negara terhadap masa lalunya yang represif dengan prospeknya untuk menciptakan tatanan yang demokratik? Apa potensi perundang-undangan untuk mendorong liberalisasi?1 Pertanyaan tentang konsepsi keadilan dalam masa-masa transisi politik belum terjawab dengan memuaskan. Perdebatan tentang “keadilan transisional” biasanya berada dalam kerangka proposisi normatif bahwa berbagai respon legal yang dilakukan perlu dinilai berdasarkan prospeknya untuk demokrasi.2 Dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang kaitan hukum dan keadilan dengan liberalisasi, terdapat dua kubu pemikiran yang saling bersaing, yaitu kaum realis dan kaum idealis, tentang kaitan antara hukum dan perkembangan demokrasi. Kaum realis menganggap bahwa perubahan politik menjadi syarat untuk terciptanya kepastian hukum, sementara kaum idealis menganggap bahwa diperlukan langkah-langkah legal tertentu untuk mendahului transisi politik. Perbedaan pandangan ini muncul dari bias keilmuan (politik vs hukum) atau dari generalisasi pengalaman-pengalaman negara tertentu ke tingkat universal. Jadi, dalam teori politik, pandangan dominan tentang proses transisi liberal menggambarkan suatu urutan yang diawali perubahan politik. Oleh karena itu, respon transisional suatu negara dijelaskan utamanya dengan batasan-batasan politik dan institusional yang relevan. Usaha mencapai keadilan dalam masa-masa itu sama sekali tergantung pada konteks yang ada (epifenomenal) 1 Karya-karya selain studi kasus atau pendekatan regional sering kali terbatas pada momen historis tertentu. Lihat misalnya John Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982 (berfokus pada masa pascaperang). Untuk pembahasan klasik tentang masalah keadilan politis, lihat Otto Kircheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. 2 Lihat Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992; Carlos Santiago Nino, Radical Evil on Trial, New Haven: Yale University Press, 1996; John Herz, “An Historical Perspective”, dalam Alice H. Henkin (ed.), State Crimes: Punishmentor Pardon, Queenstown, Md: Aspen Institute, 1998. Untuk pendekatan komparatif, lihat esai-esai dalam Guillermo O Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perpectives, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Lihat juga Juan J. Linz dan Alfred Stepan, Problems of Communist Euripe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996 (mengeksplorasi proses-proses transisi dan konsolidasi dari perspektif komparatif. Lihat misalnya Jaime Malamud-Goti, “Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?” Human Rights Quarterly 12, No. 1 (1990): 1-16. 1 dan dapat dijelaskan dengan perimbangan kekuasaan. Hukum semata-mata produk dari perubahan politik. Para realis politik biasanya meluaskan pertanyaan “mengapa negara mengambil suatu langkah tertentu” menjadi “respon apa yang mungkin”.3 Teori demikian menjelaskan mengapa keadilan transisional merupakan isu yang vital di negara-negara tertentu dan tidak di negara yang lainnya.4 Perimbangan kekuasaan yang ada, yang mengarahkan langkah-langkah transisi, dianggap menjelaskan respon legal yang ada. Namun, mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah akan “melakukan apa yang bisa mereka lakukan” tidaklah menjelaskan berbagai ragam fenomena legal transisional. Bahkan, anggapan bahwa begara melakukan apa yang bisa mereka lakukan, seperti pandangan kaum realis, hanyalah meluaskan suatu penggambaran secara deskriptif menjadi kesimpulan normatif.5 Kaitan antara respon negara terhadap masa transisinya dan prospeknya untuk liberalisasi tidak terjelaskan dengan baik. Sebaliknya, dari perspektif kaum idealis, pertanyaan tentang keadilan transisional biasanya mundur ke konsepsi-konsepsi keadilan yang universal.6 Pemikiran-pemikiran tentang keadilan retributif atau keadilan korektif tentang masa lalu dianggap menjadi syarat tercapainya perubahan liberal. Pada tingkat abstrak, beberapa gambaran ideal tersebut mungkin diperlukan untuk melakukan transisi liberal. Namun, teori seperti itu tidaklah menjelaskan dengan baik kaitan antara hukum dengan perubahan politik. Pada akhirnya, pendekatan tersebut mengabaikan ciri-ciri khas keaslian pada masa transisi. Kedua kutub idealis vs realis tentang keadilan transisi ini, seperti pula teori liberal vs kritis, berbeda dalam pandangannya tentang kaitan antara hukum dan politik. Dalam teori liberal, yang dominan dalam hukum dan politik internasional,7 hukum dianggap tidak terpengaruh oleh konteks politik8 sesuai konsepsi-konsepsi kaum idealis. Sementara, teori 3 Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1979, 1566; R. B. J. Walker, Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 123-24. Untuk ringkasan tentang pandangan realis dalam teori internasional, lihat John H. Herz, Political Realism and Political Idealism, Chicago: Chicago University Press, 1951; Martin Wight, International Theory: The Three Traditions, London: Leicester University Press untuk Royal Institute of International Affairs, 1990; J. Ann Tickner, “Hans Morgenthau’s Principles: A Feminist Reformulation”, dalam James Der Derian (ed.), International Theory: Critical Investigations, New York: New York University Press, 1995, 53, 55-57. 4 Lihat umumnya Linz dan Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation; O’Donnel et al., (eds.), Transitions from Authoritarian Rule (kumpulan esai yang umumnya berpendekatan regional). Lihat juga Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratizaton in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, 215; Stephan Holmes, “The End of Decommunization”, East European Constitutional Review 3 (musim gugur 1994), 33. 5 Untuk argument serupa, lihat Huntington, Third Wave, 231. 6 Lihat Ackerman, Future of Liberal Revolution, 69-73; E. B. F. Midgley, The Natural Law Tradition and the Theory of International Relations, New York: Barnes & Noble Books, 1975, 219-31, 350-51. 7 Anne-Marie Slaughter, “International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda”, American Journal of International Law 87 (1993), 205. Tradisi Liberal dalam Jurisprudensi melatarbelakangi pendekatan tersebut. 8 Ekspresi paradigmatik tentang pandangan teori liberal tentang hukum dan politik dapat ditemukan dalam John Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, dan John Rawls, “The Domain of the Political and Overlapping Consensus”, New York University Law Review 64 (1989), 233. Tentang kaitan antara teori tentang hak dan demokrasi, lihat Jeremy Waldron (ed.), Theories of Rights, Oxford: Oxford University Press, 1984. Lihat juga Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press, 1986; Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press, 1977. 2 hukum kritis, seperti pendekatan kaum realis, menekankan kaitan erat hukum dengan politik.9 Sekali lagi, baik teori liberal maupun kritis memang dapat menjelaskan dengan baik tentang sifat dan peran hukum dalam masa biasa. Namun, keduanya tidak dapat dengan baik menjelaskan tentang sifat dan peran hukum dalam masa perubahan politik. Karena, keduanya mengabaikan signifikansi klaim-klaim keadilan dalam masa-masa perubahan politik mendasar. Keduanya juga gagal menjelaskan kaitan antara respon-respon normatif terhadap ketidakadilan di masa lalu dengan prospek suatu negara untuk mengalami transformasi liberal. Buku ini mencoba melampaui teori-teori yang kini berlaku umum untuk menyelidiki peran hukum dalam masa-masa transformasi politik yang radikal. Ia memaparkan bahwa respon-respon legal tersebut memiliki peran yang tidak biasa dan konstitutif dalam masa-masa tersebut. Keadilan Transisional menggunakan metode induktif, dan menyelidiki berbagai respon legal untuk menjelaskan konsepsi tentang hukum dan keadilan dalam konteks transformasi politik. Keadilan Transisional diawali dengan menolak anggapan bahwa proses pergerakan menuju sistem politik yang lebih liberal demokratik berkaitan dengan suatu norma yang universdal atau ideal. Alih-alih, buku ini menawarkan cara pandang yang baru tentang kaitan antara hukum dengan transformasi politik. Fenomena-fenomena penting yang dibicarakan dalam buku ini berkaitan gelombang perubahan politik yang kini sedang berjalan, termasuk transisi dari pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur serta bekas Uni Soviet, juga dari pemerintahan militer yang represif di Amerika Latin dan Afrika. Sejauh dipandang relevan, buku ini juga mengambil ilustrasi historis, mulai dari masa kebudayaan kuno hingga masa pencerahan (Enlightenment), melalui Revolusi Prancis dan Amerika, hingga masa pasca-perang di abad ke-20 dan saat ini. Penelitian interpretatif ini dilakukan pada beberapa tingkatan. Pada satu tingkatan, saya berusaha memberikan gambaran yang lebih baik tentang praktik transisional. Studi tentang respon hukum dalam masa perubahan politik memberikan pemahaman positif tentang sifat pertanggungjawaban atas pelanggaran di masa lalu. Pada tingkat yang lain, saya menyelidiki hubungan normatif antara respon legal terhadap pemerintahan yang represif, konsepsikonsepsi tentang keadilan, dan intuisi kita tentang konstruksi negara liberal. Masalah keadilan transisional timbul dalam konteks transisi – suatu perubahan dalam tataran politik. Dengan memfokuskan penyelidikan pada tahapan “transisi”, buku ini mencoba bergeser dari perdebatan tentang istilah “revolusi” yang sering kali digunakan oleh para teoretisi dalam menganalisis peran hukum dalam perubahan politik.10 Alih-alih merupakan tahapan terakhir dalam revolusi yang tidak terjelaskan, konsep transisi yang diajukan di sini lebih luas dan lebih jelas. Batasannya adalah pada masa perubahan politik pasca-revolusi. Jadi, 9 Kumpulan penting esai-esai studi hukum kritis mencakup James Boyle, Critical Legal Studies, New York: New York University Press, 1992, dan David Kairys, The Politics of Law: A Progressive Critique, New York: Pantheon Books, 1990. Lihat juga Mark Kelman, A Guide to Critical Legal Studies, Cambridge: Harvard University Press, 1986; James Boyle, “The Politics of Reason: Critical Legal Theory and Local Social Thought”, University of Pensylvania Law Review 133 (1985), 685 (membicarakan realisme legal, teori linguistik dan teori Marxis). Untuk tinjauan kritis tentang isu legal internasional, lihat Nigel Purvis, “Critical Legal Studies in Public International Law, World Order, and Critical Legal Studies”, Stanford Law Review 42 (1990): 81. Untuk analisis kritis tentang jurisprudensi Amerika, lihat Mark Tushnet, Red, White, and Blue, Cambridge: Harvard University Press, 1988. 10 Lihat Ackerman, Future of Liberal Revolution, 11-14; Hannah Arendt, On Revolution, New York: Viking Press, 1965, 139-78. 3 masalah keadilan transisional timbul pada jangka waktu yang terbatas, antara dua pemerintahan.11 Tentu saja, karakterisasi di atas masih menyisakan pertanyaan, “transisi menuju apa?” Apa saja yang mencirikan transisi? Dalam ilmu politik, terdapat perbedaan substansial tentang arti istilah, tidak saja tentang “transisi”, namun juga batasan-batasan waktunya, “konsolidasi”, dan pada akhirnya juga, “demokrasi” sendiri. Dalam satu paradigma, “transisi” dibatasi oleh kriteria politik yang objektif, yang terutama bersifat prosedural. Jadi, untuk sementara waktu, kriteria untuk transisi menuju demokrasi difokuskan pada pemilihan umum dan prosedur lain yang terkait. Sebagai contoh, formulasi Samuel Huntington, yang mengikuti Joseph Schumpeter, mendefinisikan demokratisasi pada abad ke-20 sebagai “apabila pengambil keputusan kolektif yang terpenting dipilih melalui pemungutan suara yang jujur, adil dan diselenggarakan secara periodik.”12 Bagi yang lain, transisi berhenti apabila semua kelompok politik yang signifikan bersedia menerima kedaulatan hukum (rule of law). Selain kelompok ini terdapat pula mereka yang memiliki pandangan tentang demokrasi yang cenderung teleologis. Namun pendekatan teleologis ini mendapat kritik karena memiliki bias terhadap demokrasi ala-Barat.13 Pada masa kontemporer, penggunaan istilah transisi diartikan sebagai perubahan ke arah lebih liberal, yang serupa dengan pengertian yang digunakan dalam buku ini. Gejala liberalisasi ini banyak tergambar dalam sejarah, pada periode lebih awal dalam abad ke-20, dengan transisi demokratik di Jerman Barat, Italia, Austria, Prancis, Jepang, Spanyol, Portugal dan Yunani.14 Hingga saat ini, para pemikir politik tidaklah secara eksklusif menggunakan arahan normatif positif tersebut dalam pendefinisian mereka tentang istilah itu. Buku ini menyelidiki signifikansi bahwa pemahaman kontemporer tentang transisi memiliki komponen normatifnya yaitu dalam pergeseran rezim dari kurang demokratik menjadi lebih demokratik. Fenomenologi transisi menuju demokrasi inilah yang menjadi subjek buku ini. Tujuan saya di sini adalah mengalihkan fokus dari kriteria politik tradisional yang dikaitkan dengan perubahan menuju demokrasi, dan mulai memperhatikan sifat dan peran fenomena legal. Pendekatan konstruktivis yang diajukan dalam buku ini menunjukkan pergeseran dari definisi transisi semata-mata dalam prosedur demokratik, seperti proses pemilihan umum, ke arah penyelidikan yang lebih mendalam terhadap praktik-praktik lainnya yang menunjukkan penerimaan demokrasi liberal dan kedaulatan hukum. Penyelidikan yang dilakukan dalam buku ini membahas pemahaman normatif, melebihi pemerintahan oleh mayoritas, yang dikaitkan dengan sistem kedaulatan hukum yang liberal dalam masa transisi 11 Lihat Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 6 (mendefinisikan transisi sebagai interval antara satu rezim politik dengan rezim politik lainnya); Juan J. Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, dalam Fred I. Greenstein dan Nelson W. Polsby (eds.), Handbook of Political Science: Macropolitical Theory, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1975, Vol. III, 182-83. Untuk pandangan klasik tentang hal ini, lihat Robert Dahl, Polyarchy, New Haven: Yale University Press, 1971, 20-32, 74-80. Lihat juga Huntington, Third Wave, 7-8, Richard Gunther, et al., “O’Donnel’s ‘Illusions’: A Rejoinder”, Journal of Democracy 7, No.4 (1996), 151-53. 12 Lihat Huntington, Third Wave, 7. 13 Untuk kritik terhadap pandangan teleologis ini, lihat Guillermo O’Donnell, “Illusions and Conceptual Flaws”, Journal of Democracy 7, No. 4 (1996), 160, 163-64, dan Guillermo O’Donnell, “Illusions about Consolidation”, Journal of Democracy 7, No.2 (1996), 34. 14 Lihat umumnya Hertz, From Dictatorship to Democracy. 4 politik.15 Fenomenologi transisi ini mengarah pada kaitan erat dalam pergeseran normatif tentang pemahaman keadilan dan peran hukum dalam konstruksi transisi. Tidak semua transformasi menunjukkan tingkat “pergeseran normatif” yang sama. Bahkan transisi bisa dianggap sebagai suatu spektrum yang berkaitan dengan rezim pendahulu dan sistem nilai yang ada, yang bervariasi dari perubahan “radikal” hingga “konservatif.” Pemahaman terhadap masalah yang ditimbulkan oleh pencarian keadilan dalam konteks transisi ini memerlukan suatu diskursus yang spesifik yang ditentukan oleh dilemadilema yang khas dalam masa-masa tidak biasa ini. Dilema tentang batasan muncul dari konteks keadilan dalam transformasi politik: hukum berada antara masa lalu dan masa depan, antara melihat ke belakang dan melihat ke depan, antara retrospektif dan prospektif, antara individu dan kolektif. Dengan demikian, keadilan transisional adalah keadilan yang dikaitkan dengan konteks ini dan kondisi perpolitikan. Transisi menunjukkan pergeseran paradigma dalam konsepsi keadilan; jadi hukum memiliki fungsi yang paradoksal. Dalam fungsi sosialnya yang biasa, hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak biasa yang penuh gejolak politik, hukum menciptakan tatanan dan pada saat yang sama memungkinkan transformasi. Dengan demikian, dalam masa transisi, institusi tradisional dan predikat-predikat hukum yang biasa tidak bisa berlaku. Dalam masa-masa perubahan politik yang dinamis, respon legal menimbulkan paradigma hukum transformatif yang sui generis, khas dan unik. Tesis yang diajukan dalam buku ini adalah bahwa konsepsi keadilan dalam masa perubahan politik bersifat tidak biasa dan konstruktivis: ia membentuk sekaligus dibentuk oleh transisi itu. Konsepsi keadilan yang ditimbulkannya bersifat kontekstual dan parsial: apa yang dianggap adil dibentuk oleh ketidakadilan yang terjadi. Respon terhadap pemerintahan yang represif memiliki arti ketaatan terhadap kedaulatan hukum. Sementara suatu negara mengalami perubahan politik, peninggalan-peninggalan ketidakadilan di masa lalu menentukan apa yang bisa dianggap transformatif. Hingga titik tertentu, timbulnya respon legal tersebut merupakan transisi itu sendiri. Dengan berlanjutnya pembahasan, akan tampak bahwa peran hukum dalam masa transisi politik bersifat kompleks. Pada akhirnya, buku ini menarik dua kesimpulan: pertama, tentang sifat hukum dalam masa-masa perubahan politik yang substansial, dan kedua tentang peran hukum dalam mengarahkan transisi. Berbeda dari pandangan kaum idealis pada umumnya, buku ini justru memperlihatkan bahwa hukum dibentuk oleh kondisi politik yang ada. Namun, buku ini juga menentang pandangan kaum realis pada umumnya dengan mengatakan bahwa hukum bukanlah semata-mata produk tetapi juga ikut membentuk transisi. Kaitan antara respon-respon ini dengan masa-masa perubahan politik memajukan konstruksi pemahaman masyarakat bahwa transisi sedang berlangsung. Peran hukum dalam masa perubahan politik diteliti dengan melihat berbagai bentuknya: hukuman, penyelidikan sejarah, pemberian ganti rugi, pencopotan dari jabatan, dan penyusunan konstitusi. Dalam perdebatan keadilan transisional yang sedang berlangsung, hukuman terhadap elemen-elemen rezim lama sering kali dianggap mutlak dalam transisi demokrasi. Namun, penyelidikan tentang fenomenologi legal dalam masa perubahan politik 15 Observasi ini memiliki implikasi terhadap perdebatan-perdebatan tertentu dalam ilmu politik dan konstitusionalisme dan mungkin memiliki afinitas dengan perdebatan jurisprudensial tentang apa yang memberikan otoritas bagi hukum. Lihat Joseph Rae, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, New York: Oxford University Press, 1979, 214. 5 menunjukkan bahwa meskipun ada anggapan umum bahwa hukum memiliki kategori-kategori yang khas dan tidak bergantung pada apa pun, tetapi terdapat kemiripan antara satu dengan yang lain. Dalam buku ini, dijelaskan tentang peran operatif hukum dalam konstruksi transisi. Praktik-praktik ini menawarkan cara untuk mendelegitimasi rezim politik yang lama dan melegitimasi yang baru dengan membentuk oposisi politik dalam tatanan yang mendemokratiskan. Masing-masing bab dalam buku ini menyelidiki bagaimana berbagai respon legal dalam masa-masa perubahan politik yang substansial memungkinkan konstruksi perubahan normatif. Ajudikasi kedaulatan hukum membangun pemahaman tentang apa yang dianggap adil. Penyelidikan kriminal, administratif dan sejarah menentukan siapa pihak yang bersalah. Proyek pemberian ganti rugi mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh rezim lama kepada para korban pada khususnya, selain masyarakat secara keseluruhan. Konstitusionalisme transisional dan keadilan administratif membangun kembali parameter tatanan politik yang berubah tersebut ke arah yang lebih liberal. Analisis yang disarankan di sini berfokus pada fenomenologi hukum dalam masa perubahan politik, yang diistilahkan sebagai “jurisprudensi transisional” (teori hukum transisional). Bab I membahas kedaulatan hukum dalam masa transisi. Di negara-negara demokratik, ketaatan terhadap kedaulatan hukum bergantung pada penerapan prinsip-prinsip yang membatasi kegunaan dan penerapan hukum, namun ini bukanlah peran utamanya dalam masa transisi. Dalam masa perubahan politik yang radikal, hukum mengalami goncangan, dan kedaulatan hukum bukanlah sumber yang jelas terhadap norma ideal pada tingkat abstrak. Dalam konteks jurisprudensi transisional, kedaulatan hukum dapat dipandang sebagai skema nilai normatif yang secara historis dan politis terkait dan dielaborasikan sebagai jawaban terhadap represi politik di masa lalu yang sering kali dilaksanakan atas nama hukum. Jadi kedaulatan hukum transisional memiliki nilai-nilai yang khas dan mencirikan masa tersebut. Sementara kedaulatan hukum umumnya menunjukkan prospektivitas hukum, hukum transisional bersifat mapan dan fleksibel, melihat ke depan maupun ke belakang, karena ia menolak nilai-nilai lama yang tidak liberal dan mengambil nilai-nilai baru yang liberal. Meskipun kedaulatan hukum dan konstitusionalisme berkaitan dengan norma-norma yang memandu pembuatan hukum dalam demokrasi, pemahaman ini kurang berlaku dalam masa transisi. Meskipun terdapat banyak teori, konsep kedaulatan hukum maupun penyusunan konstitusi tidaklah dianggap sebagai sumber norma mendasar yang diidealkan. Jurisprudensi transisional dalam hal berbagai sistem hukum yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan menunjukkan keberagaman konsep kedaulatan hukum sebagai suatu tolok ukur dan kaitannya dengan pelanggarannya di masa lalu. Bab II membahas peradilan pidana dalam masa transisi. Pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran umumnya dianggap sebagai ciri mendasar dalam transformasi ke sistem politik yang lebih liberal. Hanya proses peradilan yang dianggap sebagai kunci dalam pergeseran normatif dari pemerintahan yang tidak sah ke pemerintahan yang sah. Namun pelaksanaan kekuasaan penghukuman oleh negara dalam kondisi perubahan politik yang radikal menimbulkan sejumlah dilema. Praktik pada masa transisi menunjukkan bahwa hal ini jarang dilakukan, terutama pada masa kontemporer. Jumlah pengadilan yang kecil ini menunjukkan dilema-dilema dalam menyikapi pelanggaran, yang sering kali sistemik dan berskala besar, dengan menggunakan peradilan pidana. Jadi dalam konteks transisi, pemahaman konvensional tentang tanggung jawab individual sering kali tidak dapat diberlakukan, sehingga mendorong terbentuknya format 6 legal yang baru. Sanksi parsial yang ditimbulkan, misalnya berada di luar kategori legal konvensional. Perkembangan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kaitan antara usaha pemulihan dengan pelanggaran, dan terutama beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Sanksi transisional menjelaskan kaitan antara konsep-konsep pertanggungjawaban demokratik dan hak-hak individual daam kontribusinya untuk pembangunan politik liberal. Bab III, menyelidiki proses kerja keadilan historis. Setelah masa-masa pemerintahan yang represif, masyarakat transisional sering kali mengadakan penyelidikan tentang sejarah dan pertanggungjawabannya. Penyelidikan dan narasi sejarah ini memainkan peran penting dalam transisi dari masa lalu ke masa kini. Pemaparan sejarah ini menggambarkan peninggalan masa lalu represif suatu negara dan dengan demikian menarik garis yang mendefinisikan ulang masa lalu dan merekonstruksi identitas politik suatu negara. Keadilan historis transisional menggambarkan kaitan konstruktif antara rezim kebenaran dan rezim politik, menjelaskan hubungan dinamis antara pengetahuan dengan kekuasaan politik. Bab IV membahas keadilan dan dimensi reparatorisnya. Fokus keadilan reparatoris transisional adalah reparasi atau perbaikan kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin merupakan bentuk transisi yang paling umum, banyaknya fokus pada keadilan reparatoris di berbagai kawasan mencerminkan peran dan fungsi kompleksnya dalam masa-masa perubahan politik radikal. Tindakan reparatoris tampak sebagai langkah menuju liberalisasi yang paling penting, karena hal tersebut merupakan pengakuan terhadap hak-hak individual. Perlindungan yang setara terhadap hak-hak individual merupakan dasar bagi negara liberal; maka, tindakan perbaikan ini memainkan peran konstruktif yang penting bagi suatu negara yang berusaha untuk menaati kedaulatan hukum. Dalam transisi ganda ekonomi dan politik yang mencirikan gelombang perubahan politik yang mutakhir ini, reparasi memiliki peran politik yang eksplisit untuk menengahi perubahan, dengan membentuk tonggak-tonggak baru dalam komunitas politik di tengah-tengah masa transisi. Tindakan reparatoris transisional telah melampaui peran konvensionalnya untuk memberikan ganti rugi saja, dan mendapatkan peran fungsional dan simbolis yang terkait erat pada transformasi politik suatu negara. Bab V menyelidiki keadilan administratif dan penggunaan hukum publik untuk mendefinisikan kembali parameter keanggotaan politik, partisipasi dan kepemimpinan di dalam komunitas politik. Sementara pembersihan dan pengurangan hak politik merupakan hal yang lazim setelah revolusi, pertanyaannya adalah apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang memandu tindakan-tindakan tersebut dalam transisi politik. Lebih dari respon transisional lainnya, tindakan kolektif politis yang eksplisit memberikan tantangan bagi terciptanya kedaulatan hukum dalam rezim yang sedang meliberalkan diri. Keadilan administratif menjelaskan potensi hukum untuk membangun kembali kaitan antara individu dan komunitas politik dalam masa transisi. Pemberlakuan hukum-hukum publik tersebut mendefinisikan batasan-batasan yang baru dengan dasar politik yang luas. Melalui keadilan administratif, hukum publik digunakan untuk merespon rezim lama, dan membangun kembali tatanan politik untuk menggantikannya. Respon ini merupakan contoh jurisprudensi transisional dalam bentuknya yang paling radikal. Bab VI mengeksplorasi konstitusionalisme transisional. Konstitusional transisional memiliki peran konstitutif yang konvensional, namun juga memiliki peran transformatif. Sementara kita biasanya menganggap konstitusi sebagai teks yang mendasar dan melihat ke depan; dalam masa perubahan politik radikal, konstitusi bisa berupa teks dinamis yang menengahi, sekaligus melihat ke depan dan ke belakang, dan mencakup berbagai modalitas 7 konstitusional dan tingkat-tingkat keterlibatan. Konstitusionalisme transisional, peradilan pidana dan kedaulatan hukum memiliki kedekatan dalam kesalingterkaitan bahwa normanorma yang dilindunginya berkaitan dengan masa lalu, selain juga dengan tatanan politik yang baru. Bab Penutup menggabungkan dan menganalisis berbagai cara negara demokratik baru merespon peninggalan ketidakadilan yang ada. Pola-pola yang ada pada berbagai format legal16 menunjukkan suatu paradigma “jurisprudensi transisional”. Analisis di sini menyarankan bahwa peran hukum bersifat konstruktif, dan jurisprudensi transisional timbul sebagai bentuk paradigmatik yang khas dari hukum yang responsif dan konstruktif dalam masa-masa tidak biasa yang penuh perubahan politik mendasar.17 Dalam jurisprudensi transisional, konsepsi keadilan bersifat parsial, kontekstual dan berada di tengah dua tatanan, legal dan politik. Terdapat norma-norma legal yang tidak tunggal, dan pemikiran ideal tentang keadilan selalu merupakan kompromi. Jurisprudensi transisional berpusat pada penggunaan hukum secara paradigmatik dalam konstruksi normatif rezim yang baru. Dengan mengabaikan prinsip-prinsip preskriptif yang umum dalam teori hukum dan politik, kaitan dinamis antara hukum dan perubahan politik yang dikemukakan di sini menentang retorika umum tentang arah perkembangan politik. Studi tentang peran hukum dalam perubahan politik ini menyarankan kriteria yang tidak dibatasi oleh kejujuran pemilihan umum, stabilitas institusi atau perkembangan ekonomi sebagai indikator penilaian sistem demokrasi baru.18 Respon legal merupakan pelaksana transisi dan sekaligus melambangkan transisi itu. Buku ini menawarkan bahasa jurisprudensi yang baru yang berakar pada ketidakadilan politik yang telah terjadi. Dengan memperhatikan sifat transisional jurisprudensi ini, dapat dijelaskan sifat dan peran negara dalam masa perubahan politik yang radikal. Jurisprudensi radikal juga memiliki dampak terhadap pandangan kita tentang sifat dan fungsi hukum pada umumnya. Masalah keadilan pada masa transformasi politik memiliki dampak potensial terhadap pergeseran norma-norma masyarakat dan dasar rezim konstitusional dan legal yang sedang mengalami perubahan. Masalah keadilan transisional yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan implikasi yang berkepanjangan pada suatu negara. Buku ini menawarkan perspektif yang baru untuk memahami signifikansi kontroversi yang berkelanjutan yang kini memecah masyarakat kita. Pada akhirnya perubahan mutakhir di 16 Yang dimaksud dengan “format legal” adalah prinsip, norma, ide, aturan, praktik dan juga badan-badan legislatif, administratif, ajudikasi dan penegakannya. Lihat Sally Falk Moore, Law as Process: An Anthropological Approach, Boston: Routledge, 1978, 54. Tentang signifikansi format legal, lihat Isaac D. Balbus, “Commodity Form and Legal Form: An Essay on the ‘Relative Autonomy’ of the Law”, Law and Society Review 11 (1977), 571-71. 17 Untuk pengantar pendekatan konstruktivistik, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Anchor Books, Doubleday, 1966, 19 (menjelaskan pendekatan dari perspektif sosiologi). Tentang konstruktivisme dalam hukum, lihat Pierre Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal 38 (1987), 805, 814-40. Lihat juga Roberto Mangabeira Unger, False Necessity – Anti Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, New York: Cambridge University Press: 1987, 246-52 (menganalisis respon legal dan institusional dalam “perubahan konteks”). Untuk studi tentang peran hukum dalam membangun komunitas, lihat Robert Gordon, “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review 36 (1984), 57. Lihat juga John Brigham, The Constitution of Interest: Beyond the Politics of Rights, New York: New York University Press, 1996 ( membicarakan peran hukum dalam membangun gerakan politik). 18 Lihat pada umumnya Dahl, Polyarchy; David Held, Models of Democracy, Stanford: Stanford University Press, 1987). 8 Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, bekas Uni Soviet, Afrika dan juga sejarah transisi di Eropa lainnya, menawarkan kesempatan untuk berefleksi tentang apa bentuk respon demokratik dan liberal terhadap negara non-liberal, dan secara lebih luas, potensi hukum dalam politik yang transformatif. 9 Bab I Kedaulatan Hukum dalam Masa Transisi Bab ini menyelidiki berbagai respon legal terhadap pemerintahan non-liberal dan prinsipprinsip “kedaulatan hukum” yang memandunya dalam masa-masa tersebut. Usaha untuk menaati kedaulatan hukum dalam masa gejolak politik sering kali menimbulkan dilema. Terdapat ketegangan antara kedaulatan hukum dalam masa transisi, yang sering kali melihat ke belakang selain ke depan, mapan sekaligus dinamis. Dalam dilema ini, kedaulatan hukum pada akhirnya menjadi kontekstual; alih-alih merupakan dasar tatanan hukum saja, ia juga memediasi pergeseran normatif yang mencirikan masa-masa tidak biasa tersebut. Di negaranegara demokratis, pandangan kita adalah bahwa kedaulatan hukum memiliki arti ketaatan pada aturan yang sudah ada, yang dipertentangkan dengan tindakan pemerintah secara sewenang-wenang.1 1 Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, 1944), 72 (“[P]emerintah dalam semua tindakannya diikat oleh aturan yang ditetapkan dan diumumkan sebelumnya – aturan yang memungkinkan untuk meramalkan dengan penuh kepastian bagaimana pemegang kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya dalam kondisi tertentu dan untuk merencanakan tindakan individual berdasarkan pada pengetahuan ini”.) Untuk pembicaraan tentang pemahaman umum mengenai peran kedaulatan hukum di negara-negara demokrasi sebagai batasan terhadap penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, lihat Roger Cotterell, The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy (Philadelphia: University of philadelphia Press, 1989), 113-14, yang menjelaskan bahayanya memandang negara sebagai entitas yang mengatasi hukum. Untuk penjelasan tentang kaitan antara hukum dengan demokrasi, lihat Jean Hampton, “Democracy and the Rule of Law,” dalam Nomos XXXVI: The Rule of Law, ed. Ian Saphiro (New York: New York University Press, 1995), 13. Penjelasan klasik tentang syarat minimum legalitas ditemukan dalam Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven: Yale University Press, 1964), 33-34. Ronald Dworkin menawarkan pemaparan kontemporer yang terpenting tentang teori kedaulatan hukum yang substantif. Lihat Ronald Dworkin, A Matter of Principle ( Cambridge: Harvard University Press, 1985), 11-12 (Dworkin berpandangan bahwa “konsepsi hak” dalam kedaulatan hukum mensyaratkan, sebagai bagian dari pandangan ideal tentang hukum, bahwa aturan-aturan yang tertulis mencakup dan melaksanakan hak-hak moral). Lihat juga Frank Michelman, “Law’s Republic”, Yale Law Journal 97 (1988): 1493 (yang memaparkan interpretasi modern tentang pemerintahan oleh hukum melalui reinterpretasi teori politik republikanisme kemasyarakatan (civil republicanism) . Margaret Jane Radin menggambarkan dasar filsafat dari pendekatan-pendekatan modern terhadap kedaulatan hukum dengan asumsi-asumsi berikut ini: (1) hukum tersusun atas aturan-aturan; (2) aturan berada di muka (sebelum) kasus-kasus khusus, lebih umum dari kasus-kasus khusus dan diterapkan terhadap kasus-kasus khusus; (3) hukum bersifat instrumental (aturan-aturan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya); (4) terdapat pemisahan radikal antara pemerintah dan warga negara (ada pemberi aturan dan pelaksananya, versus penerima aturan dan penaatnya); (5) manusia adalah pemilih yang rasional yang mengatur tindakan-tindakannya secara instrumental. Margaret Jane Radin, “Reconsidering the Rule of Law”, Boston University Law Review 69 (1989): 792. Lihat umumnya Cotterell, Politics of Jurisprudence (yang memberikan pengantar tentang perdebatan tentang sifat hukum); Allan C. Hutchinson dan Patrick Monahan, eds., The Rule of Law (Toronto: Carswell, 1987) (yang mengumpulkan sejumlah esai tentang kedaulatan hukum); Roger Cotterell, “The Rule of Law in Corporate Society: Neumann, Kirchheimer, and the Lessons of Weimar”, Modern Law Review 51 (1988): 126-32 (tinjauan buku). 1 Namun revolusi memiliki arti ketiadaan tatanan dan stabilitas hukum. Dilema utama dalam keadilan transisional adalah masalah kedaulatan hukum dalam masa perubahan politik yang radikal. Dari definisinya, jelas bahwa pada saat-saat tersebut terjadi perubahan paradigmatik yang mendasar dalam pemahaman tentang keadilan. Masyarakat sedang berusaha keras untuk menjawab pertanyaan “bagaimana mentransformasikan sistem politik, hukum dan ekonomi” mereka. Jika pada umumnya kedaulatan hukum memiliki arti keteraturan, stabilitas dan ketaatan pada hukum yang mapan, sejauh mana masa-masa transformasi sesuai dengan komitmen terhadap kedaulatan hukum? Pada masa-masa demikian, apa yang bisa kita artikan dengan kedaulatan hukum? Dilema tentang arti kedaulatan hukum sebenarnya tidak terbatas pada masa-masa transformasi politik dan mencakup pula dasar negara liberal. Bahkan pada masa-masa biasa, negara-negara yang demokrasinya stabil pun sering kali mengalami kesulitan untuk mengartikan ketaatan pada kedaulatan hukum. Berbagai versi dilema kedaulatan hukum di masa transisi ini tampak dalam masalah keadilan suksesor (successor justice, dalam konteks tertentu diartikan juga sebagai “keadilan pemenang”, ed.), awal konstitusional dan perubahan konstitusional.2 Dilema kedaulatan hukum ini biasanya muncul di lingkup-lingkup politik yang konteroversial, di mana nilai perubahan legal mengalami ketegangan dengan nilai ketaatan pada prinsip hukum yang menjadi preseden. Pada masa biasa, masalah ketaatan pada kontinuitas legal ini dilihat sebagai tantangan yang ditimbulkan perubahan politik dan sosial dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, ide tentang kedaulatan hukum sebagai kontinuitas legal tercakup dalam prinsip stare decisis, suatu predikat ajudikasi dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Konsep kedaulatan hukum yang mendasari konstitusi kita mensyaratkan kontinuitas, sehingga penghargaan terhadap preseden, dengan sendirinya menjadi tidak dapat diabaikan”.3 Namun dalam masa transformasi, nilai kontinuitas legal mengalami ujian yang berat. Pertanyaan tentang batasan normatif perubahan politik dan hukum yang sah bagi rezim-rezim yang mengalami transformasi sering kali ditempatkan dalam kerangka-kerangka dua kutub. Hukum sebagaimana tertulis dibandingkan hukum sebagai hak, hukum positif dipertentangkan dengan hukum kodrat [kami memilih “hukum kodrat” untuk menerjemahkan natural law, ketimbang “hukum alam”, ed.], keadilan prosedural dengan keadilan substantif, dan lain-lain. Tujuan saya di sini adalah untuk menempatkan kembali dilema kedaulatan hukum dengan memperhatikan pengalaman berbagai masyarakat dalam konteks transformasi politik. Perhatian saya bukanlah pada teori yang ideal tentang kedaulatan hukum pada umumnya. Alih-alih, saya berusaha memahami arti kedaulatan hukum bagi masyarakat yang mengalami perubahan politik berskala besar. Bab ini mendekati dilema kedaulatan hukum secara induktif dengan menempatkan kembali pertanyaan tersebut ke dalam konteks legal dan politisnya. Kita akan meneliti sejumlah kasus historis pasca-perang, dan juga preseden yang timbul dari transisi yang lebih mutakhir. Meskipun dilema kedaulatan hukum biasanya timbul dalam 2 Untuk pembicaraan pengantar tentang tema-tema umum dalam konsep kedaulatan hukum dan konstitusionalisme, lihat A. V. Dicey, Introduction to the Study of Laws of the Constitution (Indianapolis: Libery Fund, 1982), 107-22. Lihat juga E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York: Pantheon Books, 1975). 3 Planned Parenthood v. Casey, 505 US 833, 854 (1992); Lihat Antonin Scalia, “The Rule of Law as the Law of Rules”, University of Chicago Law Review 56 (1989): 1175 (yang menyarankan “kedaulatan hukum umum” di atas “keinginan individual untuk berlaku adil”). 2 konteks kejahatan (criminal), isu-isu tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang cara-cara masyarakat dalam masa-masa perubahan politik yang mendasar mengubah pandangannya tentang kaitan antara hukum, politik dan keadilan. Sebagaimana akan terlihat, ajudikasi-ajudikasi tersebut akan menunjukkan pemikiran utama tentang konsepsi kedaulatan hukum yang luar biasa dan nilai-nilai keadilan dalam masa-masa perubahan politik. Dilema Kedaulatan Hukum: Transisi Pasca-Perang Pada masa perubahan politik yang substansial, timbullah suatu dilema tentang ketaatan pada kedaulatan hukum yang berkaitan dengan masalah keadilan suksesor. Sejauh mana mengajukan unsur-unsur rezim lama ke pengadilan menunjukkan konflik inheren antara visi keadilan predesesor dan suksesor? Dengan memperhatikan konflik ini, apakah peradilan kriminal demikian bersesuaian dengan prinsip kedaulatan hukum? Dilema yang ditimbulkan peradilan kriminal suksesor mengarah pada pertanyaan lebih luas menyangkut teori tentang sifat dan peran hukum dalam transformasi menuju negara liberal. Dilema transisional ini tampak dalam perubahan-perubahan sepanjang sejarah politik. Ia tampak dalam pergeseran dari monarki ke republik pada abad ke-18, dan tampak kembali dalam peradilan-peradilan pasca-Perang Dunia Kedua. Pada masa pasca-perang, masalah tersebut menjadi subjek perdebatan hangat dalam lingkup jurisprudensi Anglo-Amerika, yaitu antara Lon Fuller dan H.L.A Hart. Keduanya berangkat dari permasalahan keadilan setelah runtuhnya rezim Nazi.4 Pembuatan teori pasca-perang demikian menunjukkan bahwa pada saat-saat perubahan politik yang signifikan, pemahaman konvensional tentang kedaulatan hukum menjadi perdebatan.5 Meskipun konteks transisional telah menimbulkan sejumlah teori tentang arti kedaulatan hukum, pembuatan teori tersebut tidak membedakan pemahaman kedaulatan hukum dalam masa-masa biasa dan transisional. Terlebih lagi, karya teoretik yang timbul dari perdebatan tersebut sering kali mundur ke model-model besar dan teridealisasi tentang kedaulatan hukum. Hal tersebut tidak dapat memperhatikan isu-isu tidak biasa yang berada dalam cakupan jurisprudensi transisional. Pengakuan suatu domein jurisprudensi transisional sendiri masih menimbulkan permasalahan tentang kaitan antara hukum dalam masa transisi dengan pada masa biasa. Perdebatan Hart-Fuller tentang sifat hukum ini berfokus pada sejumlah kasus pengadilan kolaborator Nazi di Jerman setelah perang. Isu sentral pada pengadilan-pengadilan Jerman pasca-perang adalah apakah mereka bisa menerima pembelaan yang berdasarkan 4 Lihat H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review 71 (1958); 593 (yang membela positivisme); Lon L. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart”, Harvard Law Review 71 (1958): 630 (yang mengkritik Hart karena mengabaikan peran moralitas dalam pembentukan hukum). 5 Teori-teori lain tentang sifat kedaulatan hukum dalam karya-karya Franz Neumann dan Otto Kircheimer juga mengambil masa ini sebagai titik tolaknya. Lihat Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism (Frankfurt am Main: Europäjsche Verlagsanshalt, 1977), 1933-44; Franz Neumann, The Rule of Law: Political Theory and the Legal System in Modern Society (Dover: Berg Publishers, 1986); William E. Scheuerman, ed., The Rule of Law under Siege: Selected Essays of Franz L. Neumann and Otto Kirchheimer (Berkley: University of California Press, 1996). Untuk suatu eksposisi yang menarik tentang pandangan para pakar tersebut, lihat William E. Scheuermann, Between the Norms and the Exception: The Frankfurt School and the Rule of Law (Cambridge: MIT Press, 1994), yang mencoba menerapkan analisis Neumann dan Kirchheimer ke dalam negara kesejahteraan kapitalis abad ke-20. 3 hukum pada masa Nazi.6 Sebuah isu lain yang terkait adalah apakah sebuah rezim pengganti bisa mengadili seorang kolaborator, dan dengan demikian menyatakan tidak-sahnya hukum yang berlaku pada masa terjadinya tindakan-tindakan yang dipermasalahakan tersebut. Dalam “Problem of the Grudge Informer”, dimunculkan isu hipotetis yang diabstraksikan dari kondisi pasca-perang: Rezim “Baju Ungu” telah dijatuhkan dan digantikan oleh pemerintahan konstitusional demokratik, dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah para kolaborator rezim lama harus dihukum.7 Hart, seorang tokoh positivisme hukum,8 menyatakan bahwa ketaatan pada kedaulatan hukum berarti mengakui pula bahwa hukum yang semula berlaku pada masa rezim yang lama tetap valid. Hukum tertulis yang lebih awal, bahkan bila tidak bermoral (immoral), tetap memiliki kekuatan legal dan harus diikuti oleh peradilan sesudahnya hingga ia diganti. Dalam posisi positivis yang diajukan Hart, klaimnya adalah bahwa prinsip kedaulatan hukum yang berlaku di masa pengambilan keputusan transisional harus terus berlanjut – seperti di masa normal – dengan keberlakuan sepenuhnya hukum tertulis yang ada. Dalam pandangan Fuller, ketaatan pada kedaulatan hukum berarti melepaskan diri dari rezim legal lama Nazi. Dengan demikian, para kolaborator Nazi harus dihukum berdasarkan rezim legal yang baru: Dalam “dilema yang dihadapi Jerman dalam usahanya membangun kembali institusi hukumnya yang berantakan ... Jerman harus mengembalikan penghargaan kepada hukum maupun kepada keadilan ... [K]utub-kutub pandangan yang bertentangan dihadapi dalam usahanya untuk mengembalikan kedua hal tersebut secara bersamaan.” Sementara dikotomi kedaulatan hukum disusun dalam kerangka pemikiran tentang keadilan prosedural melawan substansif, Fuller mencoba menyingkirkan konsepsi-konsepsi yang bertentangan, dengan menawarkan pandangan prosedural tentang keadilan substantif.9 Menurut badan peradilan Jerman, terdapat dikotomi dalam kedaulatan hukum antara hak legal prosedural dan hak moral. Dalam “kasus-kasus berat”, hak moral harus diutamakan. Dengan demikian, pandangan hukum yang formalis, seperti ketaatan pada hukum putatif yang telah ada (hukum positif) dapat diabaikan atas nama hak moral. Posisi hukum kodrat yang dipegang dalam peradilan Jerman ini menunjukkan bahwa keadilan transisional mensyaratkan pengabaian hukum putatif yang telah ada. Namun bagi Fuller, itu bukanlah pengabaian hukum, karena “hukum” masa lalu itu tidak dapat dianggap sebagai hukum lagi karena tidak memenuhi berbagai syarat prosedural.10 Namun perdebatan di atas tidak berfokus pada masalah khusus tentang hukum dalam konteks transisi. Pada masa pasca-perang, timbul dilema tentang kontinuitas hukum dengan masa rezim Nazi: Sejauh mana kedaulatan hukum menuntut adanya kontinuitas hukum? Sebuah perspektif transisional tentang perdebatan pasca-perang ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan hukum. Perspektif itu adalah bahwa isi kedaulatan hukum dijustifikasikan oleh konsepsi-konsepsi tentang hakikat ketidakadilan pada masa rezim represif yang telah lampau. Sifat ketidakadilan ini menjadi pertimbangan dalam berbagai 6 Lihat “Recent Cases”, Harvard Law Review 64 (1951): 1005-06 (yang mengutip Jerman, Judgement of July 27, 1949, 5 Suddeutscher Juristen Zeitung (1950): 207 (Oberlandesgericht [OLG] [Bamberg]). 7 Lihat secara umum Fuller, Morality of Law, 245. 8 Untuk eksplorasi yang mendalam tentang arti positivisme hukum, lihat Frederick Schauer, “Fuller’s Internal Point of View”, Law and Philosophy 13 (1994): 285. 9 Lihat Fuller, “Positivism and Fidelity to Law”, 642-43, 657. 10 Lihat Fuller, Morality of Law, 96-97. 4 alternatif, seperti kontinuitas sepenuhnya dengan rezim legal, diskontinuitas, diskontinuitas selektif, dan sama sekali melepaskan diri dari hukum yang ada. Bagi para positivis, kontinuitas sepenuhnya dengan rezim legal yang lama dijustifikasikan dengan kebutuhan untuk mengembalikan keteraturan prosedural, yang di masa lalu dianggap kurang terlaksana; nilai meta-kedaulatan hukum adalah due process, yang dipahami sebagai keteraturan prosedural dan ketaatan pada hukum yang ada. Klaim hukum kodrat untuk dikontinuitas legal juga dijustifikasikan oleh sifat rezim legal yang lalu, yaitu konsepsi tentang tirani di masa lalu. Menyangkut pandangan hukum kodrat terhadap kedaulatan hukum, pendekatan Fuller tampaknya lebih mendetail, karena ia mencoba menawarkan pemahaman prosedural tentang nilai-nilai keadilan substantif. Dengan imoralitasnya suatu rezim pendahulu, kedaulatan hukum perlu didasarkan pada suatu hal yang melampaui ketaatan pada hukum yang telah ada.11 Sejauh mana ketaatan pada hukum yang dibuat pada masa rezim lama yang represif konsisten dengan kedaulatan hukum? Sebaliknya, jika keadilan suksesor berarti pengadilan terhadap tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum lama tersebut, sejauh mana diskontinuitas hukum bisa dimandatkan dalam kedaulatan hukum? Konteks transisional menggabungkan pertanyaan-pertanyaan tentang legalitas kedua rezim ini dan kaitannya satu sama lain. Dalam perdebatan pasca-perang, baik posisi hukum kodrat maupun positivis berangkat dari sejumlah asumsi awal tentang sifat rezim legal pendahulu dalam masa yang tidak liberal.12 Kedua posisi ini mendapatkan justifikasi dari peran hukum dalam rezim lama; namun mereka berbeda pandangan tentang apa yang disebut prinsip legalitas yang transformatif. Argumen positivis berusaha untuk memisahkan pertanyaan legitimasi hukum dalam rezim pendahulu dan rezim kini. Respon terhadap tirani di masa lalu dianggap tidak terletak dalam lingkup hukum, melainkan dalam lingkup politik. Jika terdapat muatan yang diberikan kepada prinsip kedaulatan hukum, itu hanya berarti bahwa ia tidak boleh melayani kepentingan politis. Argumen positivis untuk ketaatan yudisial terhadap hukum yang telah ada ini bergantung pada asumsi-asumsi tertentu tentang sifat legalitas dalam rezim totaliter pendahulu.13 Justifikasi untuk terus menaati hukum yang telah ada pada masa transisi adalah bahwa dalam pemerintahan terdahulu yang represif, ajudikasi gagal mengukuhkan hukum yang mapan itu. Dalam pandangan kaum positivis, ajudikasi transformatif yang berusaha “melanggar” efek pandangan tentang legalitas yang mendukung pemerintahan otoriter akan memiliki arti ketaatan pada hukum yang telah ada. Posisi hukum kodrat memberikan penekanan pada peran transformatif hukum dalam pergeseran menuju rezim yang lebih liberal. Dalam pandangan ini, hukum putatif di bawah pemerintahan tirani tidak memiliki moralitas, dan dengan demikian tidak merupakan rezim legal yang sah. Hingga titik tertentu, dalam teori legal normatif ini, yang mereduksi masalah hukum dan moralitas, masalah transisional dalam hubungan antara dua rezim legal menjadi lenyap. Demikian pula ajudikasi yang mengikuti hukum putatif juga tak bermoral karena 11 Lihat Fuller, ibid. Untuk pembicaraan tentang perdebatan positivisme-hukum kodrat, lihat Gustav Radbruch, Rechtphilosophie (Stuttgart: Koehler, 1956); Gustav Radbruch, “Die Erneurung des Rechts”, Die Wandlung 2 (1947): 8. Lihat juga Markus Dirk Dubber, “Judicial Positivism and Hitler’s Injustice”, tinjauan Ingo Muller, “Hitler’s Justice”, Columbia Law Review 93 (1993): 1807; Fuller, Morality of Law, 23. 12 Untuk tinjauan yang baik tentang perdebatan sejarah ini, lihat Stanley L. Paulson, “Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the ‘Positivist’ Thesis”, Law and Philosophy 13 (1994): 313. 13 Lihat Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, 617-18. 5 mendukung pemerintahan yang tidak liberal. Jadi, kasus para kolaborator tersebut dikatakan sebagai “penyimpangan dalam administrasi keadilan.”14 Dari perspektif hukum kodrat, peran hukum dalam masa transisi adalah untuk merespon kejahatan yang dilakukan di bawah sistem peradilan yang lama. Karena peran judicial review dalam mempertahankan berlangsungnya penindasan (topik ini dibicarakan dalam perdebatan Hart-Fuller),15 ajudikasi sebagaimana masa-masa biasa tidak akan mencerminkan kedaulatan hukum. Teori hukum transformatif ini mendorong pandangan normatif bahwa peran hukum adalah untuk mengubah arti legalitas yang ada.16 Dalam perdebatan pasca-perang, timbul pertanyaan tentang konteks politik yang luar biasa setelah berakhirnya masa pemerintahan totaliter. Namun, kesimpulan yang didapatkan cenderung mengabstrakkan konteks dan menggeneralisasikan, seakan-akan menjelaskan atribut yang mutlak ada dan berlaku umum tentang kedaulatan hukum, dan gagal menjelaskan bagaimana masalah tersebut terkait dengan konteks transisional. Menempatkan kembali masalah tersebut bisa memberikan penjelasan terhadap pemahaman kita tentang kedaulatan hukum. Kita akan beranjak dari perdebatan pasca-perang ini ke perubahan politik yang lebih mutakhir yang menggambarkan potensi transformatif hukum. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan ketegangan antara konsepsi ideal tentang kedaulatan hukum dan kaitannya dengan konteks perubahan politik yang luar biasa. Usaha untuk menjawab dilema tentang bagaimana menaati kedaulatan hukum dalam masa-masa demikian akan mengarah pada konstruksi alternatif yang menengahi konsepsi-konsepsi tentang kedaulatan hukum transisional. Pergeseran Gambaran Legalitas: Transisi Pasca-Komunis Sisi-sisi gelap-tersembunyi dari revolusi pada masa lampau terungkap di ruang-ruang pengadilan, tempat perdebatan tentang isi transformasi politik terus berlangsung. Sejumlah kontroversi tentang peradilan kriminal yang dilakukan oleh suksesor menunjukkan dilema kedaulatan hukum transisional. Dalam buku ini, saya akan berfokus pada dua kasus. Dalam kasus pertama, sebuah hukum Hungaria mengizinkan pengadilan terhadap pelanggaran yang terkait dengan penindasan brutal oleh Soviet terhadap pemberontakan di negara itu pada tahun 1956.17 Pada kasus lainnya, Jerman-bersatu mengadili para penjaga perbatasan yang menembak warga sipil yang mencoba menyeberangi Tembok Berlin secara ilegal [semasa Jerman masih merupakan dua negara: Jerman Timur dan Jerman Barat]. Kedua kasus tersebut melambangkan kebebasan dan represi. Tahun 1956 dianggap sebagai tahun awal revolusi Hungaria, sementara Tembok Berlin dan keruntuhannya dianggap sebagai simbol utama dominasi (dan keruntuhan) Soviet. Kasus-kasus tersebut menggambarkan dilema yang terkandung dalam usaha untuk mengadakan perubahan politik yang substansial melalui hukum dan dengan merombak hukum. Meskipun kedua kasus 14 Fuller, Morality of Law, 245. Ibid. 16 Ibid., 648. 17 Lihat Zentenyi-Takacs Law: Law Concerning the Prosecutability of Offenses between December 21, 1944 and May 2, 1990 (Hungaria, 1991), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law of East and Central Europe 1 (1994): 131. Lihat juga Stephen Schulhofer et al., “Dilemmas of Justice”, East European Constitutional Law Review 1, No. 2 (1992); 17. 15 6 tersebut tampaknya menggambarkan dua cara yang bertentangan untuk meyelesaikan dilema kedaulatan hukum, mereka juga menunjukkan pemahaman serupa. Setelah terjadi perubahan politik di tahun 1991, parlemen Hungaria mengesahkan hukum yang memungkinkan pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan rezim pendahulunya yang menumpas perlawanan rakyat di tahun 1956. Meskipun peristiwa tersebut sudah lama terjadi, hukum tersebut mencabut statuta pembatasan waktu untuk pengkhianatan dan kejahatan serius lainnya,18 dan dengan demikian pelanggaran tersebut dapat diadili kembali. Perundang-undangan serupa juga disahkan di negara-negara lainnya di wilayah itu, termasuk Republik Ceko.19 Masalah statuta pembatasan waktu ini biasanya timbul setelah masa pendudukan yang lama, ketika negara berusaha mengadili kejahatan yang dilakukan pada masa rezim pendahulunya. Jadi, dalam transisi pasca-perang di Eropa Barat, masalah kedaulatan hukum yang timbul dari statuta pembatasan waktu baru timbul pada dekade 1960an,20 bukan pada masa tepat setelah perang berakhir. Kontroversi tentang hukum yang mengatasi statuta pembatasan waktu menimbulkan pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana rezim baru terikat oleh hukum rezim lama? Pengadilan konstitusional Hungaria menggambarkan dilema tersebut dalam dua kutub: antara kedaulatan hukum yang dipahami sebagai prediktabilitas dipertentangkan dengan kedaulatan hukum yang dipahami sebagai keadilan substantif. Dengan kerangka tersebut, pilihan tampaknya tidak mungkin; namun, pada akhirnya hukum yang mengatasi statuta pembatasan waktu dan rencana pengadilan terhadap kejahatan era 1956 ini dianggap tidak konstitusional. Prinsip kedaulatan hukum memerlukan prospektivitas dalam pembuatan hukum, bahkan bila pelanggaran pidana yang terberat oleh rezim lama harus dibiarkan begitu saja. Opini tersebut diawali dengan pernyataan tentang dilema yang dihadapi pengadilan tersebut: “Pengadilan konstitusional mengalami paradoks ‘revolusi kedaulatan hukum’.”21 Mengapa dikatakan sebagai paradoks? “Kedaulatan hukum”, menurut pengadilan tersebut, berarti “prediktabilitas dan pandangan ke depan”.22 Dengan melihat prinsip prediktabilitas dan memandang ke depan tersebut, larangan terhadap hukum pidana untuk menggunakan perundang-undangan retroaktif, terutama ex post facto ... secara langsung berlaku. .... Hanya dengan mengikuti prosedur legal yang formal, suatu hukum dianggap sah.”23 Pandangan dominan tentang kedaulatan hukum bagi Pengadilan Konstitusional adalah “keamanan”.24 “Kepastian hukum menuntut ... perlindungan bagi hak-hak yang sebelumnya sudah diberikan”. Hukum yang sedang direncanakan tersebut, yang akan memungkinkan pengadilan bagi bagian dari rezim lama, jelas-jelas ex post dan dengan demikian mengancam hak-hak individual untuk kedamaian. Dalam diskusinya tentang arti keamanan, pengadilan menganalogikan hak untuk mendapatkan kedamaian dengan hak milik pribadi. Meskipun 18 Lihat umumnya Zentenyi-Takacs Law. Lihat Decision of Dec. 21, 1993 (Republik Ceko, Pengadilan Konstitutional, 1993) (arsip Center for the Study Constitusionalism in Eastern Europe, University of Chicago) (mengesahkan Act on the Illegality of the Communist Regime and Resistance to It, Act No.198/1993 (1993). 20 Untuk pembicaraan tentang perdebatan statuta pembatasan waktu di Jerman, lihat Adalbert Rückerl, The Investigation of Nazi Crimes, 1945-1978: A Documentation, terj. Derek Rutter (Heidelberg, Karlsruhe: C. F. Muller, 1979), 53-55, 66-67. 21 Judgment of March 5, 1992, Magyar Kozlony, No.23/1992 (Hungaria, Pengadilan Konstitusional, 1992), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law of East and Central Europe 1 (1994): 136. 22 Ibid.,141. 23 Ibid.,141-42. 24 Ibid., 142. 19 7 perlindungan terhadap hal milik pribadi dapat diatasi oleh kepentingan negara, kepentingan tersebut, menurut pengadilan, seharusnya tidak melanggar hak individual untuk kedamaian. Dengan melindungi nilai “keamanan” dalam kedaulatan hukum dari pelanggaran oleh negara, Pengadilan Konstitusional memberikan pesan penting bahwa hak-hak milik akan dilindungi dalam transisi. Dalam masa-masa biasa, pemikiran tentang kedaulatan hukum sebagai keamanan dalam perlindungan hak-hak individual sering kali dianggap sebagai kunci, syarat minimal keberadaan kedaulatan hukum dalam negara demokrasi liberal. Namun, dalam transisi ekonomi dan legal di Eropa Tengah dan Timur, pemahaman ini merupakan transformasi yang mendasar. Jika sistem hukum totaliter menghapus atau mengabaikan batas antara individu dan negara, garis yang ditarik Pengadilan Konstitusional Hungaria ini memberikan pembatasan baru bagi negara: hak individual untuk mendapatkan keamanan. Tekanan pada perlindungan hak-hak individual ini, yang dikatakan telah dimiliki, dikonstruksikan dalam transisi. Aturan ini memberikan pesan penting bahwa rezim yang baru akan lebih liberal daripada pendahulunya. Bandingkan dengan kasus kedua. Dalam babak kedua kasus suksesornya pada abad ini [yang pertama adalah masalah Nazi, dan yang kedua adalah soal Jerman-bersatu], badan Pengadilan Jerman sekali lagi menghadapi dilema kedaulatan hukum transisional dalam pengadilan penjaga perbatasan Jerman Timur yang diadili karena penembakan di Tembok Berlin sebelum unifikasi. Pertanyaan di pengadilan itu adalah apakah pembelaan yang bergantung pada hukum rezim pendahulu dapat diterima. Pengadilan Berlin menempatkan dilema tersebut dalam kerangka ketegangan antara “hukum formal” dan “keadilan” dan menolak hukum bekas Jerman Timur karena “tidak semua hal benar karena secara formal benar”. Membandingkan hukum masa komunis dengan hukum Nazi, pengadilan menggunakan preseden pasca-perang yang menyatakan bahwa perundang-undangan yang “jahat” tidak memiliki keabsahan sebagai hukum: “terutama masa rezim Nasional Sosialis di Jerman memberikan pelajaran bahwa ... dalam kasus-kasus ekstrem, perlu diberikan kesempatan untuk memberikan penghargaan lebih tinggi pada prinsip keadilan material di atas prinsip kepastian hukum.” Secara prosedural, hak legal berbeda dengan hak moral. Sebagai “kasus ekstrem”, kasus penjaga perbatasan ini dianalogikan dengan para kolaborator di masa perang dan dengan demikian dipandu oleh prinsip adjudikatif yang sama. Pengadilan transisional di Eropa Tengah dan Timur, meskipun menghadapi isu-isu legal yang berbeda, memiliki masalah yang lazim bagi rezim suksesor: Apa implikasi terhadap kedaulatan hukum dengan mengadili tindakan-tindakan yang “legal” di masa rezim yang lampau? Seperti ditunjukkan oleh perdebatan pasca-perang di muka, pertanyaan ini menimbulkan (paling tidak) dua pertanyaan lain lagi: yang pertama tentang legitimasi hukum di masa rezim pendahulu maupun suksesor; dan, kedua tentang kaitan antara keduanya. Perdebatannya selalu tentang kedaulatan hukum sebagai norma-norma yang mapan dibandingkan dengan kedaulatan hukum yang transformatif. Dalam kasus-kasus mutakhir, seperti dalam perdebatan pasca-perang, timbullah pemahaman transisional yang baru tentang kedaulatan hukum. Kedua keputusan tersebut secara bersama-sama merupakan teka-teki yang menarik. Bagi pengadilan Berlin, nilai kedaulatan hukum yang berlaku adalah apa yang benar secara “moral,” sedangkan bagi pengadilan Hungaria, nilai kedaulatan hukum yang berlaku adalah perlindungan hak-hak “legal” yang telah ada. Dalam satu kasus, kedaulatan hukum mensyaratkan keamanan yang dianggap sebagai prospektivitas, dengan konsekuensi 8 pengampunan dari hukum pidana. Pada kasus yang lainnya, keadilan dipahami sebagai pelaksanaan hukum secara setara. Apakah kedua pendekatan ini dapat dicari titik temunya? Penyelidikan terhadap bahasa yang digunakan dalam kedua kasus suksesor tersebut menunjukkan konsepsi kedaulatan hukum yang khas dalam masa transisi. Retorika yudisial mengkonseptualisasikan masalah dengan memaparkan berbagai nilai kedaulatan hukum yang bertentangan dan tampaknya tidak dapat dipertemukan: Satu nilai dianggap relatif, yang lain dianggap esensial. Badan pengadilan transisional dalam kedua kasus tersebut mengkarakterisasikan dilema yang mereka hadapi dengan mengimbangkan dua sisi kedaulatan hukum: kedaulatan hukum sebagaimana dipahami pada umumnya versus kedaulatan hukum menurut pemahaman transformatif. Nilai mana yang akan dominan dalam kesetimbangan transisional ini akan bergantung pada konteks sejarah dan politik yang unik. Dengan demikian, setelah berakhirnya totalitarianisme di Hungaria, pandangan dominan tentang kedaulatan hukum adalah keamanan positif bagi para individu, yang berada di luar jangkauan kekuasaan negara. Di Jerman-bersatu, kedaulatan hukum transisional didefinisikan oleh jurisprudensi yang berlaku, yang merespon legalitas sejak masa fasisme. Ketika pengadilan Jerman memutuskan bahwa kasus penjaga perbatasan itu dianggap sebagai kasus “ekstrem”, ia menganalogkan pemerintahan komunis dengan Nazi. Dengan cara ini, respon legal terhadap ketidakadilan masa Perang Dunia Kedua terus memandu ajudikasi kontemporer dalam transisi dari masa pemerintah komunis. Seperti di masa pasca-perang, pengadilan Berlin pasca-komunis menggunakan prinsip hukum kodrat yang melampaui hukum lainnya. Setelah pemerintahan Nazi – suatu masa pemerintahan di mana aparat keamanan yang represif bertindak melanggar hukum dan sistem hukum itu sendiri disalahgunakan untuk menganiaya – perasaan dominan terhadap kedaulatan hukum adalah untuk perlindungan yang setara dalam pelaksanaan keadilan. Keduanya adalah pemahaman transformatif. Meskipun tidak sesuai dengan teori idealistik, preseden transisional ini menunjukkan bahwa tidak ada satu nilai tunggal dalam kedaulatan hukum yang mutlak diperlukan dalam pergerakan menuju sistem politik yang lebih liberal. Pemikiran tentang nilai-nilai kedaulatan hukum yang lebih transenden dalam masyarakat transisional di satu pihak sangat bergantung pada konteks politik dan legal yang ada di negara itu, sementara di pihak lainnya, bergantung pada peranan hukum pada masa rezim pendahulu. Terdapat perdebatan sengit antara para pakar tentang pertanyaan ini. Banyak juga dihasilkan karya-karya komparatif mutakhir tentang peran ajudikasi dalam pemerintahan yang represif pada masa Nazi di Jerman, junta militer Amerika Latin dan apartheid di Afrika Selatan. Memang terdapat banyak teori tentang peran potensial berbagai prinsip adjudikatif di bawah pemerintahan tirani, bahkan studi empiris tentang peran badan peradilan dalam masa represif. Namun prinsip-prinsip adjudikatif positivis maupun hukum kodrat tidak berkorelasi dengan penerapan kedaulatan hukum yang lebih baik pada masa-masa tersebut. Dalam berbagai konteks, para pakar mencapai kesimpulan yang beragam. Kesimpulan mereka menunjukkan bahwa variasi strategi interpretif, baik positivis maupun hukum kodrat, tidak dapat dengan sendirinya menjelaskan peran pengadilan di bawah pemerintahan yang represif. Jadi, beberapa pakar mengklaim bahwa prinsip penafsiran bebas yang dipakai para hakim Nazi mengarah pada dukungan bagi pemerintahan yang represif. Sementara beberapa pakar lainnya menekankan jurisprudensi positivis yang dipahami sebagai pemisahan antara hukum 9 dan moralitas.25 Arti kedaulatan hukum sangat bergantung pada kaitannya dengan arti sosial ketidakadilan di suatu wilayah dan responnya. Perspektif transisional tentang kedaulatan hukum yang ditawarkan dalam buku ini juga mencoba menjelaskan perbedaan yang membingungkan antara pandangan para filsuf Amerika-Anglo Saxon dan Eropa-Kontinental tentang kaitan keberlakuan antara berbagai filsafat hukum dengan represi, atau sebaliknya, dengan pemerintahan liberal. Bahwa positivisme dikaitkan dengan represi atau dengan liberalisme – di dua tempat yang berbeda – menjelaskan sifatnya sebagai respon transisional terhadap penggunaannya oleh para hakim yang “jahat”. Maka, di Amerika Serikat, positivisme sering kali diasosiasikan dengan jurisprudensi yang mendukung rezim tirani, sementara di Jerman, bukanlah positivisme, melainkan interpretasi hukum kodrat yang diasosiasikan dengan sistem peradilan Reich.26 Di satu pihak pemahaman konvensional tentang konsep tirani adalah ketiadaan kedaulatan hukum, sementara di pihak lain kedaulatan hukum transisional dalam kasus-kasus modern memberikan respon normatif yang khusus terhadap tirani kontemporer. Dari terbentuknya dalam pemahaman kuno yang diistilahkan sebagai “isonomi”, idealisasi kedaulatan hukum timbul sebagai jawaban terhadap tirani. Pada masa kuno, isonomi dibentuk sebagai jawaban terhadap tirani yang dianggap menerapkan hukum yang sewenang-wenang dan memihak. Karena tirani yang telah lewat dikaitkan dengan pembuatan hukum yang memihak dan sewenang-wenang, maka pemahaman kuno tentang kedaulatan hukum menerima baik nilai keamanan maupun keberlakuannya secara umum. Seperti pada masa kuno, ide kontemporer tentang kedaulatan hukum dibentuk dalam konteks pergeseran dari pemerintahan yang represif ke pemerintahan yang lebih liberal.27 Bila penganiayaan secara sistematis dilakukan atas nama hukum, di mana tirani adalah penganiyaan yang dilakukan secara sistematis,28 respon legal transisional adalah usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut melalui hukum. Konstruksi Transisional tentang Legalitas 25 Bandingkan Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich (Cambridge: Harvard University Press, 1991) 68, 71-78, dengan Dubber, Judicial Positivism and Hitler’s Injustice, 1819-1820, 1825. Lihat juga Richard Weisberg, Vichy Law and the Holocaust in France (New York: New York University Press, 1996). Untuk diskusi yang kaya akan gagasan, lihat Simposium, “Nazis in the Courtroom: Lessons from the Conduct of Lawyers and Judges under the Laws of the Third Reich and Vichy France”, Brooklyn Law Review 61 (1995): 1142-45. Untuk diskusi tentang Afrika Selatan, lihat David Dyzenhaus, Hard Cases in Wicked Legal Systems: South African Law in the Perspective of Legal Philosophy (New York: Oxford University Press, 1991), dan Stephen Ellman, In a Time of Trouble: Law and Liberty in South Africa’s State of Emergency (New York: Oxford University Press, 1992). Untuk pembicaraan tentang strategi interpretif badan pengadilan Amerika Latin, lihat Mark J. Osiel, “Dialogue with Dictators: Judicial Resistance in Argentina and Brazil”, Law and Social Inquiry 29 (1995): 481. 26 Untuk perbandingan yang luas tentang pendekatan Amerika dan Inggris, lihat Anthony J. Sebok, “Misunderstanding Positivism”, Michigan Law Review 93 (1995): 2055. Untuk analisis jurisprudensi di bawah rezim perbudakan, lihat Robert M. Cover, Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process (New Haven: Yale University Press, 1975), 26-29, 121-23. Untuk diskusi tentang jurisprudensi Nazi, lihat umumnya Muller, Hitler’s Justice. 27 Untuk tinjauan sejarah, lihat Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: Uninersity of Chicago Press, 1960), 162-73. Untuk sejarah intelektual tentang Rechstaat Jerman, lihat Steven B. Smith, Hegel’s Critique of Liberalism (Chicago: University of Chicago Press, 1989), 145-48. 28 Untuk diskusi terkait tentang tirani dan hukum, lihat Judith N. Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials (Cambridge: Harvard University Press, 1964), 126-27. 10 Diskusi di atas mengarah pada pemahaman kedaulatan hukum yang berbeda, dan menjelaskan suatu pemahaman tentang legalitas yang khas dalam masa transisi. Pemahaman tentang kedaulatan hukum tersebut menjembatani jurang antara pemerintahan yang tidak liberal dan liberal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai dan proses-proses tersebut menengahi transisi. Diskusi ini akan berfokus pada tiga konsep mediasi yang ada, yaitu konstruksi sosial tentang kedaulatan hukum, peran hukum internasional dalam mengatasi pemahaman hukum domestik, dan akhirnya, nilai terdalam kedaulatan hukum yaitu untuk melampaui politik yang mungkin berubah. Peran Konstruksi Sosial Salah satu konsep mediasi dalam kedaulatan hukum transisional adalah konstruksi sosialnya. Yang penting dalam menentukan kedaulatan hukum adalah budaya hukum, bukan pemikiran tentang keadilan yang abstrak dan universal.29 Pemahaman tentang kedaulatan hukum transisional yang dikonstruksikan secara sosial ini tampak dalam ajudikasi pasca-komunis. Dalam kasus penjaga perbatasan, pemahaman sosial tentang hukum yang berlaku digunakan untuk menolak pembelaan legal mereka. Validitas hukum yang lama bergantung pada praktik sosial pada suatu masa, seperti publikasi dan transparansi norma tersebut.30 “Juga di wilayah bekas Jerman Timur, keadilan dan kemanusiaan digambarkan dan dinyatakan sebagai ideal. Dengan ini, konsepsi tentang dasar hukum kodrat cukup dapat terpenuhi.”31 Kebijakan perbatasan, yang cenderung rahasia dan ditutup-tutupi bila warga asing berada di wilayah tersebut, tidak memiliki transparansi yang biasanya dikaitkan dengan hukum. Pengadilan Berlin menemukan bahwa tidak hanya kebijakan perbatasan tersebut sesuai dengan pemahaman sosial yang berlaku umum tentang hukum, namun juga bahwa pemahaman-pemahaman sosial yang berlaku umum tentang hukum di Jerman Timur serupa dengan di Jerman Barat. Para penjaga itu berada di perbatasan geografis sekaligus yuridis. Tampak bahwa peraturan tentang perbatasan ini tidak sah dengan budaya hukum yang ada. Masalah serupa timbul di Pengadilan Konstitusional Hungaria, ketika ia menekankan nilai keamanan dalam kedaulatan hukum sebagai kontinuitas hukum. Dalam konteks transisi gejolak politik, badan peradilan mengkonstruksikan pemahaman kontinuitas legal. Persepsi tentang kedaulatan hukum diciptakan oleh ketaatan pengadilan tersebut pada prosedur. Apa yang menjadikan suatu hukum dianggap positif? Teori yang diterima luas tentang kedaulatan hukum menyatakan bahwa salah satu syarat hukum adalah bahwa ia diketahui masyarakat.32 Apakah pengetahuan tentang hukum serupa dengan publikasi? Dalam masa transisi, sering kali terdapat celah antara hukum yang tertulis (law as written) dan hukum yang diterima-pahami (law as perceived). Yang menjadikan suatu hukum dianggap positif adalah keberterimaannya dalam masyarakat. Pemahaman ini memperluas, bahkan mendemokratiskan sumber legalitas dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan budaya hukum. 29 Lihat Henry W. Ehrmann, Comparative Legal Cultures (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976), 48-50; James L. Gibson dan Gregory A. Caldeira, “The Legal Cultures of Europe”, Law and Society Review 30 (196): 55-62. 30 Untuk suatu pernyataan tentang syarat hukum demikian, lihat Fuller, “Positivism and Fidelity to Law”, 638-43. Lihat juga Joseph Raz, The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System (New York: Oxford University Press, 1970) (yang merupakan usaha sistematis untuk menjelaskan syarat-syarat hukum). 31 Judgment of Jan. 20, 1992, Juristenzeitung 13 (1992): 691, 695 (Jerman Barat, Landgreicht [LG], Berlin). 32 Lihat Raz, Concept of a Legal System, 214. 11 Bahkan, di era media kontemporer dewasa ini, bisa ada berbagai sumber hukum pada suatu waktu, sekaligus beragam bentuk publikasi yang mengatasi hukum tertulis.33 Pemahaman sosial di lingkup publik adalah aturan pengakuan untuk menilai sistem hukum rezim nonliberal, suatu pemahaman tentang hukum yang independen dari keputusan pemegang kedaulatan, dan dengan demikian, kurang terpengaruh oleh gejolak politik. Dengan dipandu oleh prinsip legalitas transisional ini, legitimasi dari hukum yang dibuat rezim pendahulu akan tergantung pada pemahaman legalitas di tingkat masyarakat luas. Pemahaman bahwa kedaulatan hukum dikonstruksikan secara sosial menawarkan prinsip untuk menilai legalitas pada masa-masa peralihan antara kediktatoran dan demokrasi. Pengakuan tentang adanya celah legitimasi antara hukum tertulis dan hukum yang dipahami secara sosial memberikan cara untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam pemerintahan nonliberal. Bahkan, dengan berkurangnya kepercayaan publik dalam suatu sistem politik, bisa diharapkan bahwa celah ini akan melebar dan mendorong transisi. Peran Hukum Internasional Suatu konsep mediasi lain dari kedaulatan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional memposisikan institusi dan proses yang mengatasi hukum dan politik domestik. Pada masa gejolak politik, hukum internasional menawarkan konstruksi hukum alternatif yang bersifat kontinu dan tahan lama, meskipun mengalami perubahan politik yang substansial. Pengadilan lokal menaati pemahaman internasional ini. Potensi pemahaman terhadap hukum internasional ini menjadi kuat pada masa pasca-perang. Di Amerika Serikat, terdapat perdebatan jurisprudensial tentang apakah Pengadilan Nuremberg dan Tokyo sesuai dengan kedaulatan hukum. Hukum internasional berfungsi sebagai konsep mediasi untuk menekan dilema kedaulatan hukum yang ditimbulkan keadilan suksesor pada masa transisi dan untuk menjustifikasi legalitas Pengadilan Nuremberg dari kecemasan tentang retroaktivitas.34 Pada masa kontemporer, hukum internasional sering kali digunakan sebagai cara untuk menjembatani pergeseran pemahaman legalitas. Pada kasus-kasus pasca-komunis di muka, kontroversi tentang usaha untuk menghidupkan kembali pengadilan politik masa lalu pada akhirnya diselesaikan dengan merujuk pada konsep-konsep dalam hukum internasional. Sebagai contoh, dalam tinjauannya tentang hukum yang mengusulkan untuk membuka 33 Lihat umumnya Bonaventura De Soisa Santos, Toward a New Common Sense: Law, Science, and Politics in the Paradigmatic Transition (New York: Routledge, 1995) (yang memaparkan teori hukum dengan merujuk pada kaitan hukum dan masyarakat yang dinamis). 34 Lihat Hans Kelsen, “The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of the Axis War Criminals”, Judge Advocate Journal (Musim Gugur-Dingin 1945): 8-12, 46 (yang membicarakan sifat jurisdiksi dalam Tribunal Nuremberg dan pengadilan pasca-perang lainnya); Bernard D. Meltzer, “A Note on Some Aspects of the Nuremberg Debate”, University of Chicago Law Review 14 (1947): 455-57. (“Penerapan secara kaku dan otomatis aturan melawan retroaktivitas pada sistem hukum yang belum berkembang [seperti hukum internasional] akan, tentu saja, memperlebar jurang atara perasaan moral yang berkembang di masyarakat dan institusi legalnya yang terbelakang”). Lihat umumnya Stanley L. Paulsen, “Classical Legal Positivism at Nuremberg”, Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 132 (yang menyatakan bahwa penolakan pembelaan Nazi oleh Tribunal Nuremberg dijustifikasikan oleh penolakannya terhadap positivisme legal klasik); Quincy Wright, “Legal Positivism and the Nuremberg Judgment”, American Journal of International Law 42 (1948): 405 (menyatakan bahwa kritikan terhadap peradilan Nuremberg yang dianggap menerapkan hukum ex post facto berakar pada teori hukum internasional positivis yang dipegang para pengkritik tersebut). 12 kembali kasus politik yang terkait dengan pemberontakan 1956, Pengadilan Konstitusional Hungaria memutuskan bahwa pembukaan kembali kasus tersebut merupakan diskontinuitas dengan hukum yang ada. Diskontinuitas demikian, menurut Pengadilan Konstitusional, mengancam pemahaman tentang legalitas di masa suksesor; tidak boleh ada prinsip untuk meninggalkan hukum-hukum tertentu saja secara selektif. “Legitimasi berbagai sistem (politik) yang berbeda selama setengah abad terakhir tidaklah relevan ...; dari sudut pandang konstitusionalitas hukum, ia bukanlah kategori yang signifikan.”35 Dalam tinjauan yudisial berikutnya, pengadilan mengesahkan statuta baru yang memungkinkan pengadilan terhadap kasus 1956 yang berkaitan dengan “kejahatan perang” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” menurut hukum internasional.36 Kedaulatan hukum memerlukan adanya kontinuitas. Kontinuitas demikian dianggap ada dalam norma hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa yang Berkaitan dengan Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang,37 yang norma-normanya mengatasi hukum domestik. Keputusan serupa diambil di Polandia, yang membatalkan perpanjangan statuta pembatasan waktu, kecuali terhadap pelanggaran yang dianggap melanggar hak asasi manusia internasional.38 Anggapan bahwa hukum internasional diutamakan di atas hukum domestik tidaklah jelas, karena Konstitusi Hungaria tidak menyatakan dengan jelas tentang prioritas hukum internasional dibandingkan dengan hukum domestik. Namun Pengadilan Konstitusional menunjukkan bahwa ia akan menafsirkan konstitusi dipandu oleh norma-norma internasional, menyatakan bahwa “aturan-kedaulatan hukum internasional yang diakui bersama akan diutamakan”. Beberapa konstitusi secara eksplisit menyatakan adanya prioritas tersebut.39 Di berbagai negara di wilayah itu, hukum internasional menjadi dasar untuk interpretasi yudisial terhadap kebijakan penghukuman, karena norma-norma tersebut dianggap lebih utama dari hukum-hukum rezim lama yang telah terpolitisasi. Dalam kasus penjaga perbatasan Jerman, keputusannya secara eksplisit didasarkan pada hukum internasional.40 35 Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka) Lihat Act on Procedures Concerning Certain Crimes Committed during the 1956 Revolution (Hungaria, 1993) (arsip Center for the Study of Constitusionalism in Eastern Europe, University of Chicago). 37 Lihat “Geneva Convention Relative on the Protection of Civilian Persons in Time of War”, 12 Agustus 1949, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 75, No. 973 (1950); 287; “Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity”, 11 November 1970, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 754, No. 10823 (1970): 73. 38 Di Polandia, masalah statuta pembatasan waktu baru terselesaikan dengan konsensus konstitusional. Lihat Konstitusi Republik Polandia, Pasal 43 (yang disahkan Dewan Nasional, 2 April 1997), yang menyatakan bahwa sejauh suatu pelanggaran merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka tidak diikat oleh pembatasan waktu. 39 Resolution of the Hungarian Constitutional Court of Oct. 12, 1993 on the Justice Law (Kasus 53/1993) (arsip Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, semula di University of Chicago). Lihat Konstitusi Hungaria, Pasal 7 ayat 1 (“Sistem hukum Republik Hungaria ... menyesuaikan hukum nasional dan statuta negara dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional”). Bandingkan dengan Konstitusi Yunani, Pasal 28 ayat 1 (yang menyatakan bahwa kedaulatan hukum internasional diutamakan terhadap hukum domestik yang berlawanan). 40 Lihat Border Guards Prosecution Cases (Jerman Barat, Bundesgerichtshof [BGH]), diterjemahkan dalam International Law Reports 100 (1995): 380-82 (yang mempertimbangkan International Covenant on Civil and Political Rights, 19 Desember 1966, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 999, No. 14688 (1976): 171 (yang menyatakan bahwa ketertiban domestik 36 13 Pada masa gejolak politik, hukum internasional berperan sebagai konsep mediasi yang berguna. Penempatan dilema kedaulatan hukum dapat dengan mudah digeser dari pertentangan antara positivisme dengan hukum kodrat. Dengan berdasar pada hukum positif, namun juga menerapkan nilai-nilai keadilan yang dikaitkan dengan hukum kodrat, hukum internasional dapat memediasi dilema kedaulatan hukum. Norma-norma hukum internasional positif ditentukan melalui konvensi, traktat dan kebiasaan.41 Terlebih lagi, dengan mencakup kejahatan yang paling mengerikan ke dalam lingkupnya, hukum internasional menawarkan suatu sumber transendensi normatif. Sebagai gambaran adalah konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dibicarakan lebih lanjut pada bab tentang peradilan kriminal, yang menunjukkan dua nilai yang bertentangan dan sekaligus berkaitan, dalam respon normatif universal terhadap penganiayaan dalam berbagai konteks kebudayaan.42 Sementara hukum internasional mempertahankan pemahaman umum tentang kedaulatan hukum sebagai kemapanan, ia juga memungkinkan transformasi. Dengan demikian, ia memediasi transisi. Prinsip-prinsip hukum internasional berfungsi untuk mendamaikan dilema batasan minimal hukum pada masa transformasi politik. Kedaulatan Hukum sebagai Pembatasan terhadap Politik Ciri utama kedaulatan hukum dalam masa perubahan politik adalah bahwa ia mempertahankan adanya kontinuitas dalam format legal, sementara pada saat yang sama memungkinkan perubahan normatif. Sifat hukum dan ajudikasi yang terpolitisasi pada masa sebelumnya menjustifikasi adanya sedikit diskontinuitas dalam transisi. Pemahaman tentang kedaulatan hukum yang anti-politik ini adalah tema umum dalam kontroversi transisional kontemporer yang dibicarakan di muka. Pengadilan para penjaga perbatasan dikatakan sebagai “kasus ekstrem”, yang menjustifikasi diabaikannya pertimbangan kedaulatan hukum yang biasa.43 Pengadilan Jerman mengangkat apa yang benar secara moral di atas kebenaran secara politis. Kasus-kasus lain di wilayah tersebut menunjukkan interpretasi yudisial terhadap kedaulatan hukum secara serupa. Invalidasi Hungaria terhadap hukum pengadilan 1956 membatasi kebijakan anti-komunis yang terpolitisasi. melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh traktat internasional). Lihat umumnya Stephan Hobe dan Christian Tietje, “Government Criminality: The Judgement of the German Federal Constitutional Court of 24 October 1996”, German Yearbook of Internatioanal Law 39 (1996): 523. Lihat juga Krisztina Morvai, “Retroactive Justice Based on International Law: A Recent Decision by the Hungarian Constitutional Court”, East European Constitutional Review (musim gugur 1993/musim dingin 1994): 33; “Law on Genocide and Crimes against Humanity Committed in Albania during Communist Rule for Political, Ideological and Religious Motives”, diterjemahkan dalam Human Rights Watch, Human Rights in Post-Communist Albania (New York: Human Rights Watch, 1996), lampiran A (menjadi dasar untuk mengadili bekas Komunis). 41 Lihat Statute of the International Court of Justice, U. S. Statutes at Large 59 (1945): 1031, Pasal 38 (1). Untuk pembahasan tentang pemahaman positivis, lihat Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice (Dordrecht, Belanda; dan Boston: M. Nijhoff, 1991; didistribusikan di Amerika Serikat dan Kanada oleh Kluwer Academic Publishers), 35-36. Peran kebiasaan dalam pembentukan hukum internasional dijelaskan dalam Michael Akehurst, “Custom as a Source of International Law”, British Yearbook International 47 (1974-1975): 1. Untuk diskusi terkait tentang elemen-elemen hukum positif dan hukum kodrat dalam hukum internasional, lihat Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials, 126-28. 42 Lihat J. M. Balkin, “Nested Opposition”, Yale Law Journal 99 (1990): 1669 (tinjauan buku). 43 Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas), 693. 14 Untuk mengesahkan hukum yang akan memperpanjang waktu untuk menuntut kejahatan yang dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya, Pengadilan Konstitusional Ceko menyatakan bahwa hukum tersebut akan membongkar kebijakan penghukuman dan penerapan keadilan masa lalu yang terpolitisasi. Hukum tersebut akan menangguhkan pembatasan waktu selama empat puluh satu tahun (jangka waktu antara 25 Februari 1948 dan 29 Desember 1989) untuk tindakan-tindakan yang semula tidak diadili atau dihukum karena “alasan politis”.44 Jika di bawah rezim represif pelaksanaan keadilan dilakukan semata-mata atas kepentingan politis,45 pandangan ini paling jelas dilawan dengan penerimaan suatu nilai kedaulatan hukum yang jelas mencerminkan pandangan normatif yang terlepas dari kondisi politik peralihan. Konstruksi kedaulatan hukum transisional yang terbebas dari politik memiliki sejumlah kedekatan dengan pemahaman kedaulatan hukum yang berlaku pada saat-saat normal. Namun, konteroversi tentang keadilan transisional dalam konteks yang amat terpolitisasi merupakan kasus yang berat untuk tetap taat terhadap kedaulatan hukum. Meskipun terdapat perubahan politik yang radikal, tujuannya adalah kedaulatan hukum yang tidak dimotivasi oleh politik. Jurisprudensi transisional memberikan harapan untuk mencapai kedaulatan hukum yang anti-politik. Badan Pengadilan Transisional Pada masa transformasi politik, masalah legalitas terpisah dari masalah teori hukum sebagaimana berlaku di negara-negara demokratis di masa biasa. Terdapat pertanyaanpertanyaan teknis di luar inti tentang legitimasi rezim yang baru, termasuk sifat dan peran badan pengadilan transisional. Pilihan prinsip ajudikasi akan menimbulkan pertanyaan terkait tentang di mana, sebagai masalah institusional, letaknya kerja-kerja transformatif: pada badan pengadilan atau legislatif? Inilah pertanyaan yang akan dicoba untuk dijawab. Dilema keadilan transisional timbul pada masa perubahan politik substansial. Jika sistem hukum berada dalam perubahan, tantangan terhadap perubahan umum tentang kedaulatan hukum tentu saja amat berat. Tantangan pada masa transisi pasca-perang tidaklah seberat tantangan pada masa transisi dari pemerintahan komunis di masa kini, yang merupakan masa transformasi ekonomi, politik dan sekaligus hukum. Pada masa ini, pengadilan konstitusional yang baru dibentuk harus menanggung beban institusional untuk menciptakan pemahaman baru terhadap kedaulatan hukum. Beban transformasi untuk menjadi sistem yang taat kedaulatan hukum ini hingga titik tertentu diberikan kepada badan pengadilan, terutama badan pengadilan konstitusional yang baru itu. Respon transformatif serupa bisa dilihat pada transisi mutakhir yang lain, seperti di Afrika Selatan. Konstitusi transisional Afrika Selatan membentuk Pengadilan Konstitusionalnya yang baru.46 44 Lihat Decision of Dec. 21, 1993 (dikutip di catatan kaki 19 di atas). Untuk tinjauan tentang sifat pengambilan keputusan demikian dalam sistem politik non-liberal, lihat diskusi tentang decisionism dalam Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, terjemahan George Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 53-66. 46 Untuk penjelasan tentang awal perkembangan ini, lihat Herman Schwartz, “The New East European Constitutional Courts”, Michigan Journal of International Law 13 (1992): 741. Lihat Ruti Teitel, “Post Communist Constitutionalism: A Transitional Perspective”, Columbia Human Rights Law Review 26 (1994): 167. Untuk kumpulan esai tentang pengadilan konstitusional Eropa Timur, lihat Irena Grudzinska-Gross, ed., Constitutionalism in East Central Europe (Bratislava: Czecho-Slovak Committee of the European Cultural 45 15 Mungkin akan timbul pertanyaan apakah kontinuitas dengan rezim pendahulu adalah suatu pertanyaan bagi para hakim masa transisi atau suatu pertanyaan politis yang perlu diperdebatkan secara lebih luas. Ketika pertanyaan ini muncul pada transisi kontemporer pasca-komunis, badan pengadilan mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Isu ini menjadi pertanyaan politik di Jerman-bersatu. Namun, dalam pertimbangannya tentang sah tidaknya hukum Republik Demokratik Jerman (GDR) untuk kasus penjaga perbatasan, Pengadilan Berlin mengabaikan kesepakatan politik antara kedua negara Jerman tersebut (Jerman sebelum bersatu). Traktat Unifikasi mempertimbangkan kontinuitas hukum pidana Jerman Timur, dengan syarat bahwa ia diterapkan bagi tindakan pidana yang dilakukan pada masa sebelum reunifikasi. Namun, pengadilan menolak pembelaan para penjaga perbatasan yang berdasarkan pada hukum Jerman Timur.47 Dengan demikian, pengadilan menunjukkan independensinya dari legislatif dan agenda politiknya. Namun, respon transformatif terhadap masalah politis tidak terlalu diperlukan di Jerman-bersatu, dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, karena konteks transisinya. Demikian pula, ketika Pengadilan Konstitusional Hungaria menolak hukum pengadilan 1956, ia memberikan pesan yang jelas tentang independensinya dari elemen-elemen politik negara itu.48 Keputusan-keputusan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang kedaulatan hukum yang dibentuk oleh badan pengadilan transisional yang berusaha mencapai independensi dari politik. Para teoretisi politik sering kali membedakan rezim liberal dengan non-liberal atas dasar konstitusi mereka; peran konstitusionalisme transisional dibicarakan lebih mendalam pada bab 6. Namun, penelitian yang dilakukan di sini menunjukkan bahwa apa yang menunjukkan sifat liberal dari suatu rezim politik bukanlah spesifiknya suatu tatanan institusional tertentu, namun lebih pada sejauh mana terdapat pelaksanaan dan pemahaman terhadap kedaulatan hukum. Meskipun konstitusi era komunis menggambarkan hak-hak, umumnya hak-hak tersebut hanya ada di atas kertas dan jarang dilaksanakan. Jadi, setelah komunisme, pengesahan piagam baru tentang hak asasi tidak akan memberikan transformasi yang signifikan bagi kedaulatan hukum. Sebagai respon terhadap ketidakadilan ini, ada sejumlah pengadilan konstitusional untuk melaksanakan konstitusi yang baru.49 Peran ini bagi badan pengadilan adalah respon legal “kritis” yang secara jelas menandakan transformasi terhadap sistem konstitusional demokrasi liberal. Pengadilan konstitusional membantu transformasi menuju sistem kedaulatan hukum dengan beberapa cara. Pertama, pengadilan timbul dari sistem kekuasaan negara yang tersentralisasi; sebagai forum baru yang dibentuk secara khusus pada masa perubahan dan transformasi politik, pembentuknya dengan sendirinya menandakan berakhirnya tatanan politik masa lalu. Kedua, akses terhadap pengadilan konstitusional melalui litigasi memberikan kemungkinan partisipasi dalam sistem demokrasi yang baru mulai berkembang. Sejalan dengan waktu, akses ke pengadilan akan memungkinkan masukan dari masyarakat ke dalam interpretasi konstitusional, memungkinkan pemahaman di tingkat masyarakat terhadap pembatasan pemerintah dan perlindungan terhadap hak individual. Akses masyarakat ke pengadilan untuk pelaksanaan hak-hak individual merupakan simbol potensial keterbukaan Foundation, 1994). Lihat juga Konstitusi Afrika Selatan, Bab VII (dibicarakan pada bab tentang keadilan konstitusional dalam buku ini). 47 Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas). 48 Lihat Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka). 49 Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 169-76. 16 pemerintahan yang baru.50 Ketiga, karena pengadilan konstitusional memiliki mandat eksplisit untuk melakukan tinjauan yudisial, mereka adalah pengawal tatanan konstitusional yang baru. Di banyak negara di Eropa, aturan jurisdiksional yang luas memungkinkan tinjauan yudisial yang abstrak dan akses untuk tinjauan oleh para aktor politik, seperti presiden, atau oleh faksi minoritas melalui badan legislatif.51 Pengadilan di wilayah tersebut aktif dalam menginterpretasikan norma-norma konstitusional baru di bawah konstitusi yang ada, di bawah mandat umum untuk menjunjung kedaulatan hukum. Sebagai contoh adalah tinjauan Pengadilan Konstitusional Hungaria terhadap hukum tentang kebijakan pengadilan yang dijelaskan di muka.52 Pengadilan konstitusional memiliki potensi untuk membatasi kekuasaan negara dan mendefinisikan ulang hak-hak individual, sehingga menciptakan budaya hak. Melalui ajudikasi transformatif, badan pengadilan transisional menerapkan prinsip tinjauan yudisial yang aktif terhadap perubahan normatif dan sistem kedaulatan hukum yang lebih liberal. Praktik adjudikatoris transformatif memunculkan pertanyaan penting: dengan anggapan bahwa badan pengadilan transisional menanggung beban transformasi kedaulatan hukum, hingga sejauh mana praktik tersebut bersesuaian dengan peran badan pengadilan di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan? Di negara-negara demokrasi pada masa biasa, pengambilan keputusan kehakiman yang aktif (activist judicial) biasanya dianggap tidak sah, karena dua alasan. Pertama, retroaktivitas dalam pengambilan keputusan kehakiman bertentangan dengan kedaulatan hukum sebagai kemapanan hukum.53 Kedua, pengambilan keputusan kehakiman dianggap mengintervensi demokrasi; tidak seperti pengambilan keputusan di badan legislatif, pengambilan keputusan kehakiman tidak memiliki legitimasi yang didapatkannya dari proses yang demokratis.54 Pertanyaannya adalah apakah penolakan yang berdasar pada kondisi normal tersebut bisa pula diterapkan pada ajudikasi masa transisi. Pandangan kita tentang tempat yang tepat untuk melakukan penyusunan hukum bergantung pada asumsi implisit tentang demokrasi dan pertanggungjawaban demokratik yang tidak bisa begitu saja diterapkan terhadap rezim non-liberal atau rezim yang sedang bergeser dari pemerintahan demikian. Di negara-negara demokrasi mapan pada masa biasa, pandangan kita adalah bahwa penyusunan hukum transformatif harus dilakukan oleh badan legislasi, dan bukan oleh ajudikasi. Badan pengadilan tidak membuat hukum, karena pembuatan hukum dengan cara tersebut dianggap tidak sesuai dengan demokrasi, yaitu pembuatan hukum oleh badan perwakilan dengan persetujuan mayoritas.55 50 Lihat Ethan Klingsberg, “Judicial Review and Hungary’s Transition from Communism to Democracy: The Constitutional Court, the Continuity of Law, and the Redefinition of Property Rights”, Brigham Young University Law Review 1992 (1992): 62 (membicarakan akses yang sangat terbuka yang ditimbulkan oleh aturan Hungaria yang sangat permisif). Negara tersebut bukanlah satu-satunya di wilayah tersebut yang memperimbangkan partisipasi para aktor politik dalam litigasi konstitusional. 51 Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism,” 186-87. 52 Lihat Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka). 53 Lihat R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 84. 54 Ibid., 84, 138. 55 Menyangkut paradigma tradisional tentang badan pengadilan, lihat umumnya Martin Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago: University of Chicago Press, 1981). Lihat juga Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (New York: Clarendon Press, 1989), 31-34 (mengamati bahwa para hakim harus “membuat hukum” dengan menafsirkannya namun membedakan tugas ini dari tugas para legislator, yang bertindak dengan prosedur yang berbeda). Untuk pernyataan klasik tentang peran badan pengadilan dalam demokrasi, lihat umumnya Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch (New Haven: 17 Pada masa transisi, masalah legalitas jauh lebih signifikan. Masa-masa transformasi politik sering kali disertai dengan perubahan legal radikal. Gelombang perubahan politik yang paling mutakhir, yang berkorelasi dengan transformasi ekonomi (pada perubahan pascakomunis) menuntut adanya reformasi hukum secara besar-besaran. Masalah konvensional tentang ketiadaan pertanggungjawaban demokratik yang ditimbulkan oleh pembuatan hukum oleh badan yudisial menjadi tidak terlalu penting dalam masa gejolak politik. Pada masa demikian, badan legislatif transisional sering kali tidak dipilih melalui pemilihan yang bebas, dan juga tidak memiliki pengalaman dan legitimasi sebagaimana dimiliki badan serupa di masa-masa normal.56 Satu alasan lain mengapa badan pengadilan tidak dianggap sebagai badan pembuat hukum adalah ketiadaan kompetensi dan kapasitas institusionalnya. Masalah ini timbul, misalnya, dalam perdebatan pasca-perang tentang pembentukan kedaulatan hukum. Menurut pandangan positivis, beban transformasi hukum dianggap sepantasnya ditanggung oleh badan legislatif, sementara pandangan hukum kodrat memberikan beban tersebut kepada ajudikasi. Namun, perdebatan pasca-perang ini tidak cukup memasukkan konteks transisional di dalamnya. Karena masa-masa perubahan politik biasanya disertai dengan gejolak hukum, kontroversi dalam masa-masa tersebut sering kali dicirikan dengan ketiadaan hukum yang relevan.57 Terlebih lagi kontroversi pada masa-masa tidak biasa tersebut sering kali perlu diselesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Sementara dalam masa biasa, pembuatan hukum dengan mempertimbangkan kasus demi kasus tampaknya terlalu lambat dan terlalu fleksibel, pada masa transisi, pengambilan keputusan hukum oleh badan pengadilan sering kali bisa lebih cepat daripada oleh badan legislatif, yang biasa diperlambat oleh kurangnya pengalaman dan karena terlalu kompromistis. Terlebih lagi, dalam konteks gejolak politik, badan pengadilan sering kali lebih kompeten dalam membahas penyelesaian kontekstual, kasus demi kasus, terhadap kontroversikontroversi transisional.58 Memang, pengambilan keputusan yudisial memungkinkan perubahan substansial dan menjadi ciri ambivalensi hukum pada masa-masa demikian. Pertanyaan tentang institusi mana yang paling kompeten dan sah bersifat kontekstual dan tergantung pada sejarah ketidakadilan di negara yang bersangkutan. Terakhir, ajudikasi transformatif dapat memperbaiki badan pengadilan itu sendiri. Dengan mengubah prinsip dan praktik ajudikatif, institusi yang pada masa sebelumnya tunduk (compromised) secara politis atau ideologis dapat memperbaiki dirinya. Dalam kasus-kasus high profile, sebuah badan pengadilan yang semula tunduk itu dapat mengubah dirinya dengan mengubah prinsip ajudikasi yang ia gunakan. Mekanisme institusional perbaikan diri ini terutama penting bila badan pengadilan semula mendukung pemerintahan yang represif.59 Yale University Press, 1986); Jesse H. Choper, Judicial Review and the National Political Process (Chicago: University of Chicago Press, 1980); dan John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review (Cambridge: Harvard University Press, 1980). 56 Pada awal pergeseran politik, parlemen transisional biasanya merupakan peninggalan dari masa represif sebelumnya. Lihat Andrew Arato, “Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern Europe”, Cardozo Law Review 14 (1993): 674-75. 57 Untuk pembicaraan ilustratif tentang transisi Rusia menuju berkurangnya kekuasaan Negara, lihat Stephen Holmes, “Can Weak-State Liberalism Survive?” (makalah dipresentasikan di Colloquium tentang Teori Konstitusional di New York University School of Law, musim semi 1997, arsip penulis). 58 Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 182-85. 59 Lihat misalnya Müller, Hitler’s Justice, 201 (membicarakan badan pengadilan yang terkompromi di Jerman pasca-perang). 18 Namun, bahkan bila badan pengadilan bukanlah institusi yang kompromistis, masih ada implikasi berguna lain dari ajudikasi transformatif. Teori ajudikasi yang dikaitkan dengan pemahaman tentang kedaulatan hukum pada masa biasa tidak dapat diterapkan pada masa transisi. Pandangan umum kita tentang sifat dan peran ajudikasi berkait dengan asumsi awal tentang kompetensi dan kapasitas badan legislatif dan pengadilan di masa biasa, yang tidak bisa diterapkan untuk masa-masa yang tidak stabil. Kasus-kasus yang dibicarakan di muka menunjukkan peran luar biasa bagi pengadilan dengan menjalankan prinsip ajudikasi transformatif. Pada masa perubahan politik, perhatian pada demokrasi dan legitimasi, yang dalam kondisi normal akan membatasi ajudikasi yang aktif (activist adjudication), malah akan mendukung ajudikasi seperti itu sebagai alternatif terhadap politisasi yang lebih besar terhadap hukum. Praktik Ajudikatif Transformatif: Beberapa Kesimpulan Bab ini diawali dengan memaparkan bahwa terdapat dilema khusus tentang ketaatan terhadap kedaulatan hukum pada masa-masa perubahan politik. Pemahaman umum tentang kedaulatan hukum sebagai ketaatan terhadap hukum yang telah mapan mengalami ketegangan dengan pemahaman transformatif terhadap kedaulatan hukum. Saya akan membahas prinsip normatif manakah dari kedaulatan hukum yang dikaitkan dengan ajudikasi pada masa perubahan politik. Pada masa tidak biasa ini, seperti dibicarakan di muka, norma-norma kedaulatan hukum tidaklah universal. Ketegangan yang timbul dari masalah ketaatan terhadap kedaulatan hukum pada masa itu diselesaikan dengan sejumlah konsep mediasi. Legalitas pada masa tersebut dikonstruksikan secara sosial; sebagiannya, dibuat oleh hakim. Eksplorasi terhadap preseden-preseden pada masa itu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kedaulatan hukum dikonstruksikan di dalam konteks transisional. Dengan mencegah politisasi hukum, prinsip kedaulatan hukum ini memandu pengambilan keputusan hukum interim (sementara) di jalan menuju demokrasi. Pengakuan terhadap prinsip ajudikasi transformatif dalam masa transisi politik memiliki implikasi yang signifikan terhadap teori hukum yang lazim tentang kedaulatan hukum. Pertama, pengakuan terhadap prinsip tersebut dapat memberikan jawaban yang memuaskan, ketika teori hukum yang lazim gagal memperhatikan signifikansi berbagai pemahaman normatif tentang kedaulatan hukum dalam masa transisi. Selain itu, kedaulatan hukum transisional merupakan kritik implisit terhadap teori-teori dominan tentang sifat dan peran hukum. Dalam teori politik liberal, suatu pedoman tentang kedaulatan hukum adalah bahwa pembuatan hukum melalui ajudikasi dianggap sebagai hal yang netral dan otonom dari politik.60 Pemahaman liberal ini ditantang karena dengan memperhatikan kondisi di mana hukum transformatif berperan, yang mendefinisikan kedaulatan hukum berdasarkan kaitan konstruktifnya dengan politik di masa lalu. Prinsip ajudikasi transformatif mungkin memberikan tantangan lebih serius bagi teori hukum kritis. Teori hukum kritis sering kali dikritik karena terlalu jauh mereduksi kaitan hukum dan politik. Dengan demikian, pendekatan teoretik ini sering kali tidak mampu 60 Lihat misalnya Ronald M. Dworkin, Law’s Empire (Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1986); Bruce R. Douglass, Gerald M. Mara dan Henry S. Richardson, ed., Liberalism and the Good (New York: Routledge, 1990). 19 menjelaskan mengapa, atau dalam kondisi mana, hukum memiliki klaim terhadap masyarakat. Meskipun teori hukum kritis mengklaim bahwa terdapat penurunan penurunan kedaulatan hukum secara umum,61 pembicaraan di muka menunjukkan bahwa hal ini paling mungkin terjadi dalam konteks politik transisi. Kedaulatan hukum transisional menegaskan peran bagi ajudikasi yang sangat terpolitisasi. Dari perspektif teori hukum kritis, tantangan yang diberikan oleh praktik ajudikatoris transformatif yang dibicarakan di sini adalah tantangan yang diberikan oleh pembatasan aksi politik yang dilakukan oleh hukum.62 Jurisprudensi pada masa tersebut membentuk transisi. Pemahaman normatif tentang hukum bervariasi secara luas dengan konteks politik transisi. Dalam negara-negara demokrasi transisional, terdapat tempat dan peran untuk keputusan hukum yang dipolitisasi secara terbatas. Proses legal memungkinkan perubahan rasional dan terukur. Di luar ajudikasi, perubahan normatif yang membangun legalitas baru dicapai dengan bentuk-bentuk hukum lainnya. Jadi, peran sanksi pidana yang biasanya terbatas untuk menghukum kesalahan individual lebih besar dalam masa transisi, seperti juga respon legal terhadap kejahatan negara dan dengan demikian menyerang akar tidak legitimnya pemerintahan pendahulu. Respon legal demikian berfungsi untuk mengutuk dan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Pada bab berikut ini, saya akan beralih ke penggunaan peradilan pidana dalam masa transformatif. 61 Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition (New York: Harper and Row, 1978), 4-5; Richard L. Abel, ed., The Politics of Informal Justice (New York: Acdemic Press, 1982), 267; David M. Trubek, “Turning Away from Law?” Michigan Law Review 82 (1984): 825. 62 Untuk eksplorasi tentang berbagai pemikiran yang bertentangan mengenai kedaulatan hukum dari perspektif liberalisme dan teori hukum kritis, lihat umumnya Andrew Altman, Critical Legal Studies: A Liberal Critique (Princenton: Princenton University Press, 1990). 20 Bab 2 Peradilan Pidana Dalam bayangan publik, keadilan transisional lazim dikaitkan dengan pengadilan dan penghukuman penguasa sebelumnya. Simbol-simbol kuat revolusi Inggris dan Prancis dari pemerintahan monarki ke republik adalah pengadilan Raja Charles I dan Louis XVI. Setengah abad setelah terjadinya simbol utama kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua adalah pengadilan Nuremberg. Kemenangan demokrasi terhadap pemerintahan militer di transisi Eropa Selatan diwakili oleh pengadilan terhadap para kolonel di Yunani. Pengadilan junta Argentina menandakan akhir puluhan tahun pemerintahn represif di seluruh Amerika Latin. Gelombang transisi kontemporer dari pemerintahan militer, di Amerika Latin dan Afrika, demikian pula dari pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan bekas blok Soviet, telah memunculkan kembali perdebatan tentang apakah perlu dilakukan penghukuman. Penghukuman mendominasi pemahaman kita tentang keadilan transisional. Bentuk hukum terkeras ini melambangkan pertanggungjawaban dan kedaulatan hukum; tetapi, dampaknya jauh melebihi peristiwa itu sendiri. Tinjauan terhadap masa transisi menunjukan bahwa peradilan pidana yang dijalankan oleh pemerintahan pengganti atau suksesor menimbulkan banyak pertanyaan sukar bagi masyarakat yang telah terkena akibat dari kekerasan masa lalu itu, sehingga sering kali peradilan tersebut tidak dilaksanakan. Perdebatan tentang peradilan pidana transisional diwarnai oleh dilema yang sukar: menghukum atau memberikan pengampunan? Apakah penghukuman adalah tindakan yang melihat ke belakang sebagai pembalasan, atau ekspresi pembaruan kedaulatan hukum? Siapa yang paling perlu bertanggung-jawabuntuk represi yang telah terjadi? Sejauh mana tanggung jawab terhadap represi dapat dibebankan kepada individu, dibandingkan kepada kolektif, rezim atau bahkan seluruh masyarakat? Dilema utama yang terkait erat dengan transisi adalah bagaimana cara bergeser dari pemerintahan non-liberal dan sejauh mana pergeseran ini dipandu oleh pandangan konvensional tentang kedaulatan hukum dan tanggung jawab individual yang dikaitkan dengan demokrasi yang sudah mapan. Ketegangan inti yang timbul di sini adalah tentang penggunaan hukum untuk memajukan transformasi, yang dipertentangan dengan perannya dalam ketaatan terhadap legalitas konvensional. Sejauh mana peradilan pidana transisional dikonseptualkan dan diajudikasi sebagai hal yang kontekstual terhadap masyarakat tertentu, atau dipandu oleh kedaulatan hukum biasa yang dipergunakan demokrasi mapan? Dilema utama ini bisa diperluas ke banyak dilema lainnya. Apa tatanan legal yang paling relevan? Militer atau sipil? Internasional atau nasional? Dan, tanpa mempedulikan apa pun tatanan legal yang relevan, sampai sejauh manakah pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana diproyeksikan ke belakang? Apakah seluruh proyek keadilan ini sama sekali bersifat ex post? Siapa yang diminta pertanggungjawaban, dan untuk pelanggaran apa? Dilema-dilema transisi ini dibicarakan dalam bab ini. Ini dibicarakan, dan dicapai kompromi transisioanl dalam bentuk “sanksi pidana terbatas”, yang pada hakikatnya adalah bentuk penghukuman yang simbolis. 1 Dasar Argumen Peradilan Pidana dalam Masa Transisi Mengapa harus menghukum? Argumen utama untuk memberikan hukuman pada masa gejolak politik bersifat konsekuensional dan melihat ke depan. Dikatakan bahwa dalam masyarakat dengan masa lalu yang buruk yang baru saja keluar dari pemerintahan yang represif, pengadilan suksesor memberikan dasar yang kuat untuk membangun tatanan liberal yang baru. Pada masa-masa itu, sebagai variasi justifikasi hukum “utilitarian” yang konvensional, dasar bagi memberikan hukuman adalah kontribusinya bagi kebaikan bersama.1 Namun tidak seperti argumen konvensional untuk menghukum pada masa normal yang cenderung berfokus pada pelaku atau dampak hukuman bagi masyarakat, misalnya sebagai penggentar, argumen untuk menghukum pada masa transisi memiliki bentuk lain. Alih-alih memberikan argumen untuk menghukum secaraafirmatif, argumennya diberiakan secara negatif – apa yang akan terjadi bila tidak ada penghukuman? Di sinilah konteks politik khas dari masa transisi memainkan peranan. Sementara argumen menentang impunitas, yaitu argumen tentang akibat dari kegagalan memberikan hukuman, juga digunakan pada masa biasa,2 argumen ini menjadi lebih kuat pada masa transisi. Karena, dengan kondisi ketiadaan hukum pada masa sebelumnya, jauh lebih banyak harapan terhadap tindakan-tindakan menuntut pertanggungjawaban berdasarkan kedaulatan hukum. Ketidakadilan di masa lalu ini, perlu diingat, sebagian besar dipicu dan didukung oleh negara. Dengan latar belakang ini, argumen menentang impunitas mendapat arti yang baru. Dalam konteks ini, pelaksanaan peradilan pidana dianggap merupakan cara terbaik untuk memperbaiki “keadilan” negara di masa lalu dan memajukan transformasi normatif ke sistem yang taat kedaulatan hukum. Rezim yang represif sering kali dicirikan oleh tindakan pidana, seperti penyiksaan, penahan secara sewenang-wenang, penghilangan, eksekusi di luar hukum, yang semuanya didukung oleh negara. Bahkan, bila kejahatan di masa lalu dilakukan oleh pelaku privat, negara sering kali masih terimplikasi, baik melalui kebijakan penindasan, kegagalannya melindungi warga negara, atau dalam menutupi tindakan pidana dan impunitas. Konteks transisi, terutama tentang keterlibatan negara dalam tindakan pidana, memberikan argumen kuat untuk menghukum dibandingkan impunitas. Namun, paradoks terjadi ketika konteks transisional tersebut menimbulkan dilema signifikan terhadap penggunaan hukum pidana sebagi respon yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara. Pemberian hukuman memiliki peran historis untuk melaksanakan norma-norma kedaulatan hukum dalam konteks kesalahan negara di tingkat internasional. Argumen mendasar untuk pengadilan suksesor memiliki sejarah yang panjang hingga abad pertengahan, yang mengambil dari norma-norma hukum internasional konsep tentang keadilan terhadap kekerasan politik yang tidak sah. Pengadilan sudah lama digunakan untuk menerapkan normanorma hukum internasional tentang ketidakadilan dalam perang. Pembebanan tanggung jawab pidana terhadap pemimpin politik pendahulu karena mengadakan perang yang melanggar hukum, atau mirip dengan itu, pemerintahan negara yang buruk, adalah benang merah pengadilan suksesor terhadap tiran-tiran polis yang dijelaskan oleh Arisoteles dan pengadilan 1 Lihat Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press, [1769], 1995; Jeremi Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Vol. 2, Darien, Conn: Hafner Publishing [1823], 1970 (berteori bahwa hukuman diperlukan untuk kebaikan bersama). 2 Lihat Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, New York: Oxford University Press, 1979, 400-01. 2 Raja Charles I serta Louis XVI, hingga pengadilan serupa pada masa kontemporer: Pengadilan Nuremberg, pengadilan kejahatan perang Tokyo, pengadilan kolonel di Yunani dan pengadilan junta militer Argentina. Dalam sejarahnya, pengadilan suksesor berdasarkan pada konsep tirani yang didasarkan pada pengkhianatan; pihak yang melanggar hukum dalam perang adalah pihak yang kalah.3 Pemahaman awal tentang kaitan hukum pada keadilan ini diformulasikan kembali di Nuremberg, ketika pengadilan digunakan untuk memberikan pesan normatif yang jauh lebih besar daripada sekadar pengadilan terhadap rezim asing yang terkalahkan, untuk membedakan kekerasan yang “adil” dari yang “tidak adil”. Pada masa kontemporer, peradilan pidana suksesor digeneralisasikan keluar dari penggunaannya semasa pasca-perang ke transisi lain, di mana kekuatan normatif utamanya adalah pengutukan terhadap kekerasan politik di masa sebelumnya. Delegitimasi terhadap kekerasan yang dilakukan rezim pendahulu ini berada di luar domain pengadilan pasca-perang. Pengadilan terhadap para pimpinan politik digunakan untuk mengkonstruksikan arti ketidakadilan negara. Pemberian hukuman didukung dengan dasar bahwa hal tersebut memajukan identitas politik suatu masyarakat dalam transisi sebagai pemerintahan demokratis oleh negara yang menaati hukum. Teori kontemporer biasanya menjustifikasi penghukuman dalam negara-negara transisi karena potensi perannya untuk membangun tatanan politik baru yang demokratis.4 Pengadilan suksesor dikatakan memiliki fungsi politik untuk menarik garis batas antarrezim, memajukan sasaran politik transisi tersebut dengan mendelegitimasi rezim pendahulu, dan melegitimasi rezim penggantinya. Pengadilan Raja Charles I dan Louis XVI, demikian pula Nuremberg, pada dasarnya adalah tindakan politik. Seperti ditulis Michael Walzer, “Kaum revolusioner harus menamatkan rezim lama: ini berarti bahwa mereka harus melakukan proses ritual untuk ... secara terbuka mengutuk ideologi rezim lama.”5 Tentang pengadilan Raja Louis XVI, Walzer menyatakan bahwa “regisida secara terbuka merupakan cara yang amat kuat untuk memecahkan mitos-mitos rezim lama, dan dengan demikian, merupakan titik berdirinya sistem yang baru.”6 Pengadilan terhadap raja tersebut memiliki arti politik, dengan menunjukkan bahwa ia tidak berada di atas hukum.7 Melalui pengadilan suksesor, hukum menerapkan kesetaraan semua orang di muka hukum, dan dengan demikian melakukan pergeseran normatif yang mendasar dalam pergeseran dari monarki ke republik. Pengadilan suksesor juga dibela dengan dasar serupa oleh Judith Shklar: “Pengadilan sebenarnya bisa mencapai tujuan liberal, dengan mendorong nilai-nilai legalistik sedemikian rupa untuk memberikan kontribusi pada politik konstitusional dan sistem hukum yang baik.”8 Dalam perkataan Otto Kirchheimer, pengadilan memungkinklan “pembangunan tembok yang permanen dan jelas antara awal yang baru dan tirani yang lama.”9 3 Lihat David Lagomarsino dan Charles T. Wood, The Trial of Charles I: A Documentary History, Hanover, N.H: University Press of New England, 1989, 25; Michael Walzer (ed.), Regicide and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI, terjemahan Marian Rothstein, New York: Cambridge University Press, 1974, 88. 4 Untuk argumen kontemporer, lihat Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute, Human Rights Violations of a Prior Rezim”, Yale Law Journal 100 (1991): 2537. 5 Walzer (ed.), Regicide and Revolution, 88. 6 Ibid., 5. 7 Ibid., 78. 8 Judith N. Shklar, Legalism, Morals, and Political Trials, Cambridge: Harvard University Press, 1964, 145. 9 Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Wesport, Conn: Greenwood Press, 1961, 308. 3 Dalam banyak teori politik yang diterima, pengadilan suksesor dianggap memiliki potensi untuk berperan penting dalam menarik garis antara tirani lama dan awal pemerintahan baru. Peradilan pidana menawarkan legalisme normatif yang membantu menjembatani masamasa lemahnya kedaulatan hukum. Proses pengadilan memberikan cara untuk mengekspresikan secara terbuka kutukan terhadap kekerasan di masa lalu dan legitimasi kedaulatan hukum yang diperlukan untuk konsolidasi demokrasi di kemudian hari. Peradilan pidana suksesor biasanya dijustifikasi oleh tujuan konsekuensialis tentang pembentukan kedaulatan hukum dan konsolidasi demokrasi.10 Pandangan demikian yang khas pada masa transisi ini dijelaskan di sini sebagai justifikasi “demokratis” terhadap hukuman yang utamanya berdasar pada tujuan transisi. Proses peradilan pidana tepat digunakan untuk menekankan pesan inti liberal tentang keutamaan hak dan kewajiban individual. Peran pengadilan suksesor pada masa-masa demikian tidaklah terlalu mendasar, namun lebih sebagai cara transisi. Penggunaan peradilan pidana untuk menarik garis antar-rezim menimbulkan dilema yang sukar tentang kaitan antara hukum dan politik. Sementara pengadilan dalam konteks politik ditujukan untuk mencapai tujuan politik – berkaitan dengan pesan paling utama dari keadilan transisional untuk memberikan dasar bagi transisi politik, untuk membantah norma-norma politik pendahulu dan untuk membangun tatanan politik yang baru – hal-hal tersebut bertentangan dengan pemahaman konvensional tentang kedaulatan hukum. Dilema inti tersebut berkaitan dengan ciri utama transisi: konteks politik pergeseran normatif. Dilema yang ditimbulkan oleh pergeseran politik dari pemerintahan non-liberal menjadi liberal ini sangat terkait dengan masalah retroaktivitas berbagai norma yang relevan selama perubahan rezim dan penerapan aturan-aturan normatif rezim yang baru terhadap tindakan rezim lama. Bila dilema ini diteliti lebih lanjut, konsekuensinya menjadi amat paradoksal: agar pengadilan dapat memenuhi potensi konstruktif mereka, prosesnya harus dijalankan dengan legalitas penuh seperti pada negara demokrasi yang telah mapan di masa biasa, dan bila proses pengadilan tidak berjalan dengan adil, dampaknya bisa menjadi negatif, memberikan pesan keadilan politis yang keliru dan mengancam demokrasi yang baru tumbuh. Dengan demikian, pengadilan suksesor berada pada batasan yang tipis antara tercapainya ketaatan pada kedaulatan hukum, atau risiko berlanjutnya keadilan politis. Kesukaran untuk menyelesaikan dilema yang ditimbulkan oleh penggunaan hukum pidana untuk tujuan kedaulatan hukum transisional ini menjelaskan mengapa banyak rezim pengganti yang tidak menggunakan cara ini, dan menjelaskan timbulnya bentuk-bentuk sanksi pidana yang lebih “terbatas.” Pesan normatif transisional ini paling jelas terdengar melalui tatanan hukum internasional, karena kekuatannya terletak pada mekanisme normatif dengan kapasitas untuk menanggapi kekerasan politik luar biasa yang berada di luar tatanan hukum biasa. Dengan demikian, ia cocok untuk mengekspresikan pesan transisional dari pergeseran normatif. Anehnya, kekuatan ini merupakan sekaligus kelemahannya, karena sifatnya yang tidak biasa ini, hingga titik tertentu, menempatkan di luar legalitas konvensional, dan dengan demikian, tidak menaati pemahaman normal tentang kedaulatan hukum dalam memperkuat transformasi demokratik. 10 Lihat Ruti Teitel, “How Are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” (makalah dipresentasikan sebagai latar belakang untuk diskusi di Council on Foreign Relations, mengkritik bahwa demokrasi menjustifikasi kewajiban untuk menghukum), New York, 17 Mei 1990. 4 Warisan Nuremberg Sejak Perang Dunia Kedua, pandangan tentang keadilan suksesor telah didominasi oleh nilainilai yang didapatkan dari pengadilan Nuremberg. Signifikansi pengadilan tersebut paling mudah ditempatkan dalam konteks sejarah dan politisnya, dengan melihat keadilan transisional pasca-Perang Dunia Pertama dan kegagalan kebijakan pengadilan nasionalnya.11 Kebijakan keadilan di Versailles melatarbelakangi kebijakan pengadilan di Nuremberg dan menjelaskan mengapa pengadilan nasional dianggap terlalu politis dan tidak dapat bekerja. Kegagalan pengadilan nasional pasca-Perang Dunia Pertama dianggap bertanggung-jawab untuk timbul kembalinya agresi Jerman. Rasa bersalah yang berkaitan dengan perang dan ditanggung oleh seluruh negeri dianggap mencegah transisi menuju demokrasi yang berkelanjutan. Pandangan bahwa keadilan nasional bersifat terlalu politis ini menjadi latar belakang kebijakan pasca-perang sebelumnya, dengan akibat yang akan terlihat sepanjang sisa abad ke-20. Melalui Pengadilan Nuremberg, inti dari respon pasca-perang menjadi norma yang diterima. Seperti setelah Perang Dunia Pertama, mekanisme pertanggungjawaban adalah pengadilan, dan pelanggaran utama yang dipermasalahkan adalah agresi. Namun, kesamaan antara kedua pengadilan tersebut hanya sampai di situ. Perbedaan signifikan dari Nuremberg adalah pertanggungjawaban tetap ada di tangan pihak sekutu; jurisdiksinya bukan nasional, melainkan internasional. Dan, alih-alih menghukum sebuah negara, tujuannya adalah membebankan pertanggungjawaban individual. Namun, kita akan melihat bahwa realitas pengadilan Nuremberg bergeser dari mandatnya semula. Warisan Nuremberg menjadi lebih rumit dengan celah yang tampak antara idealisasi ilmiah tentang preseden tunggal ini dan realitas sejarahnya: setengah abad kemudian, pembicaraan tentang pengadilan tersebut masih terdengar. Bagaimana keadilan dicapai di Nuremberg, termasuk ketidaksesuaian dengan prosedur umum, menjadi identik dengan keadilan suksesor. Sebuah anomali hukum pada waktu itu, pengadilan Nuremberg masih tetap merupakan preseden yang menjadi anomali, dengan melihat praktik-praktik suksesor lainnya di abad ini. Namun, satu cara untuk memahami signifikansi Nuremberg sebagai preseden adalah dengan membedakan berbagai pemahaman tentang preseden tersebut, misalnya antara Nuremberg sebagai proses, dalam sidang Tribunal Militer Internasional dan proses peradilan pidana internasional, dan aspek doktriner, yaitu keputusan-keputusan yang disahkan. Diawali dengan aspek preseden persidangan, di sinilah presedennya terlemah. Dalam lima puluh tahun setelah Nuremberg, meskipun sering kali dibicarakan tentang baiknya tribunal serupa, terutama di masa perang, jarang sekali dilaksanakan proses pengadilan, meskipun, sebagaimana kita mendekati akhir abad ke-20, mulai tercipta momentum untuk pembentukan pengadilan pidana internasional yang permanen.12 11 Untuk tinjauan tentang pengadilan-pengadilan nasional yang gagal, lihat George Gordon Battle, “The Trials Before the Leipsic Supreme Court of Germans Accused of War Crimes”, Virginia Law Review 8 (1921): 1. 12 Komisi Persiapan Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah menyelesaikan tugasnya dengan mengesahkan kerangka kerja untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional. Lihat U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.6-18, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.21, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.19, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.3/Rev.1. Hingga diterbitkannya buku ini [dalam versi Inggris, ed.], Sidang Diplomatik Tingkat Tinggi PBB untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah bersidang di Roma antara 15 Juni sampai 17 Juli 1998, untuk memfinalkan dan menyetujui konvensi untuk pembentukan pengadilan tersebut. Lihat 5 Nilai kuat preseden Nuremberg bukanlah pada proses, namun pada cara ia membentuk pemahaman umum tentang peradilan pidana transisional. Pada lima puluh tahun terakhir, Nuremberg membentuk pemahaman ilmiah dominan tentang peradilan suksesor, dengan pergeseran pendekatan dari proses nasional ke proses internasional, juga dari kolektif ke individual. Peradilan pidana suksesor model Nuremberg merupakan forum yudisial, prosedur pidana multinasional, dan juga pelanggaran seperti “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang sama sekali baru dan menginternasional. Pendekatan keadilan suksesor ini sangatlah internasional berkaitan dengan pelanggaran yang relevan, dasar jurisdiksi dan prinsip legal. Sebuah tinjauan historiografis menunjukkan dampak kuat preseden tersebut pada literatur ilmiah, terutama tentang bagaimana pertanggungjawaban dikonseptualisasi dalam hukum internasional. Tinjauan terhadap bibliografi tentang pertanggungjawaban bagi kejahatan berat oleh negara menunjukkan bahwa literatur tentang respon internasional terhadap kekejaman sejak Perang Dunia Kedua, terutama dalam bahasa Inggris, berkembang dengan pesat, sementara studi komparatif tentang pengalaman nasional cenderung diabaikan.13 Secara historis, satu alasan untuk banyaknya studi tentang keadilan suksesor pasca-perang adalah bahwa ia mencerminkan perkembangan hukum internasional yang paralel. Di masa pasca-perang terjadi kerja sama yang tanpa preseden dalam Tribunal Militer Internasional di Nuremberg, terbentuknya PBB, dan juga pengesahan berbagai konvensi dan resolusi tentang kejahatan internasional. Beratnya pelanggaran yang dilakukan para Nasional Sosialis (Nazi) dan kolaborator mereka mendorong tercapainya konsensus internasional yang sebelumnya tidak pernah ada. Optimisme dan momentum dari konsensus baru tentang kejahatan internaional tersebut, dan juga kerjasama internasional dalam proses pengadilan, menimbulkan harapan untuk terbentuknya badan hukum pidana internasional tentang penindasan oleh negara, yang akan dilaksanakan oleh suatu tribunal internasional. Literatur hukum mencerminkan kemajuan dalam struktur hukum internasional dan keputusan-keputusannya. Literatur hukum internasional yang tumbuh pesat tentang respon terhadap penindasan oleh negara mencantumkan tema-tema dan istilah dari suatu hukum pidana internasional yang mulai tumbuh: dari cara pendefinisian kejahatan, signifikansi Tribunal Militer Internasional, ekspansi jurisdiksi terhadap tindakan-tindakan tertentu, dan mungkin yang paling penting, timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang baru dalam komunitas internasional. Semua ini menjadi bidang kajian penting yang berlanjut hingga kini. Namun justifikasi historis untuk menempatkan keadilan suksesor dalam kerangka hukum internasional kini cenderung berkurang. Harapan masa pasca-perang untuk berkembangnya hukum pidana internasional hingga kini belum terpenuhi. Antusiasme yang muncul bersamaan dengan kemajuan hukum internasional menurun dengan kesadaran tentang umumnya Cristopher Keith Hall, “The First Two Sessions of the U.N. Preparatory Commitee on the Establishment of an International Criminal Court”, American Journal of International Law 91 (1997): 177; James Crawford, “The ILC Adopts a Statute for an International Criminal Court, American Journal of International Law 89 (1995): 404 (membicarakan rancangan statuta Komisi Hukum International [ILC] untuk membentuk pengadilan pidana internasional); Bernhard Graefrath, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court”, European Journal of International Law 1 (1990): 67 (membicarakan usaha PBB untuk membentuk pengadilan pidana internasional). [Mahkaham yang dimaksud itu, yaitu Mahkamah Pidana Internasional, saat ini telah didirikan, ed.] 13 Lihat Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986. 6 kurang efektifnya mekanisme internasional untuk merespon kekejaman. Sistem penghukuman internasional (international penal law) tetap berada pada kondisinya yang tidak berkembang: masih belum ada sistem hukum pidana internasional (international criminal code). Dan, meskipun berulang kali diserukan pembentukan pengadilan pidana internasional atau bahkan jurisdiksi internasional, forum tersebut masih belum dibentuk. Baru belakangan ini timbul konsensus di masyarakat internasional yang mendukung prinsip pengadilan pidana internasional yang permanen untuk dibentuk sebelum akhir abad ke-20.14 Namun, pemberian jurisdiksi kepada badan internasional terhadap pelanggaran pidana selain genosida masih ditentang oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Bahkan dalam kontroversi hukum internasional yang berkaitan dengan hal-hal non-pidana, di mana jurisdiksi internasional telah disepakati, tampaknya tidak akan tercapai kesepakatan.15 Dengan demikian, kejahatan internasional yang telah didefinisikan belum tentu disertai oleh jurisdiksi universal. Dengan ditempatkannya negara di Mahkamah Internasional sebagai aktor dan dengan intensif untuk menjadikan negara tetap kebal terhadap tuntutan, struktur hukum internasional kini belum membantu pelaksanaan konvensi menentang genosida dan jaminan lainnya dari hukum internasional. Literatur yang menyerukan penambahan norma-norma internasional dan mekanisme penerapan jauh lebih maju daripada parameter konsensus pascaperang dan sistem hukum internasional yang ada.16 Celah antara definisi kejahatan menurut hukum internasional dan mekanisme penerapannya masih tetap lebar. Namun, meskipun dengan sifatnya yang luar biasa, hukum internasional memberikan panduan normatif yang sedikit banyak memediasi banyak dilema keadilan transisional. Dilema Transisional dan Pergeseran Paradigma Nuremberg Paradigma keadilan dan istilah-istilah hukum internasional yang diciptakan di Nuremberg, meskipun memiliki kelemahan, masih tetap menjadi kerangka perdebatan tentang keadilan suksesor. Dalam sistem hukum internasional, dilema keadilan suksesor berhasil diselesaikan. Pandangan tentang ketidakmampuan keadilan nasional melepaskan diri dari politik timbul dari sejarah kebijakan pasca-Perang Dunia Pertama, dengan dampak yang terasakan di kemudian hari. Secara abstrak, dilema keadilan suksesor tampaknya paling bisa diselesaikan dengan merujuk pada sistem hukum yang otonom. Sementara dalam skema hukum nasional, pertanyaan tentang keadilan tampaknya tidak bisa dilepaskan dari politik, dari perspektif hukum internasioanal, pertanyaan tentang keadilan dapat dipisahkan dari politik internasional.17 Bahkan bila peradilan internasional seluruhnya bersifat ad hoc, seperti tentang kekejaman dalam konflik Balkan, paling tidak ia dianggap kurang politis dibandingkan alternatif-alternatif lainnya. Hukum internasional dianggap bisa mengangkat keadilan dari konteks nasionalnya yang terpolitisasi. Hukum Internasional dan Dilema Keadilan Retroaktif 14 Lihat catatan kaki 12 di atas. Sebuah contoh yang buruk adalah penolakan Amerika Serikat terhadap jurisdiksi Mahkamah Internasional dalam kasus yang diajukan Nikaragua. Lihat Nicaragua v. United States, 1984 ICJ 392 (1984). 16 Lihat Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, New York: Times Books, 1998. 17 Untuk komentator dengan posisi ini, lihat misalnya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York: Penguin Books, 1964. 15 7 Dilema transisional yang utama adalah bagaimana mengkonsepkan keadilan dalam konteks pergeseran normatif besar-besaran. Masalah ini diredam oleh hukum internasional, karena hukum internasional memberikan kontinuitas dalam hukum, dan terutama, standar pertanggungjawaban. Jadi, pemantapan nilai-nilai hukum internasional pada masa pascaperang dianggap memberikan dasar jurisdiksional yang melampaui batasan hukum pidana domestik. Hukum internasioanal tampaknya memberikan cara untuk mengatasi masalah retrospektivitas yang endemik dalam keadilan transisional. Standar dan forum internasional menjunjung kedaulatan hukum, sementara memenuhi pula prinsip keadilan dan imparsialitas. Nilai aksi legal internasional yang mengikat dan menjadi preseden sering kali dianggap lebih tinggi daripada tindakan domestik. Perbedaan hukum domestik berarti bahwa kejahatankejahatan tertentu akan bisa dihukum di negara-negara tertentu, namun tidak di negara lainnya. Terlebih lagi, kejahatan yang benar-benar mengerikan, seperti pembantaian massal, tidak bisa ditanggapi dengan baik oleh hukum nasional, karena kejahatan demikian dikonseptualkan secara amat berbeda dengan pelanggaran serupa dalam hukum nasional. Kejahatan-kejahatan tertentu, seperti penyiksaan, sering tidak bisa ditanggapi dengan memuaskan atau tidak diakui oleh hukum nasional, meskipun gerakan untuk mencantumkan standar-standar hukum internasional ke dalam hukum domestik mungkin dapat meredam masalah ini. Hukum pidana internasional memberikan cara yang jelas untuk mengkonseptualkan kemungkinan paradoksal tentang pertanggungjawaban rezim yang jahat di bawah hukum. Itulah sebabnya hukum pidana internasional membangun analogi historis keadilan pasca-perang yang mendominasi pengadilan Nuremberg. Ia mendefinisikan keadilan di Nuremberg, dengan pelanggaran yang paling utama: melakukan peperangan. Dan, menurut piagam pembentukannya, tujuan pengadilan tersebut adalah untuk mengadili penjahatpenjahat perang terpenting untuk pelanggaran – yang terkait dengan perang. Dan forum untuk pengadilan tersebut berbentuk tribunal militer internasional, dan pelanggaran utamanya adalah agresi. Bahkan “kejahatan terhadap kemanusiaan”, kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil, hanya diadili di Nuremberg apabila terkait dengan perang. Batasan yang penuh kehatihatian dalam pelaksanaan tribunal ini mempertahankan pandangan ketidakadilan negara sebagai ketidakadilan yang dilakukan oleh negara asing. Garis tipis yang membatasi pengadilan Nuremberg ini akan memiliki dampak yang akan membatasi potensi preseden tersebut bagi keadilan transisional. Dilema Kejahatan Dilakukan Negara tetapi Pertanggungjawabannya Bersifat Individual Peradilan pidana transisional menimbulkan dilema besar tentang bagaimana membebankan pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengimplikasi negara dalam kebijakan represif. Jurisprudensi internasional memberikan standar dalam bentuk prinsip-prinsip Nuremberg. Diformulasikan setelah pengadilan tersebut atas permintaan Sidang Umum PBB, “Prinsip Nuremberg” merupakan pemurnian dari keputusan-keputusan di Nuremberg dan merupakan titik penting dalam konseptualisasi pertanggungjawaban untuk kejahatan negara. Untuk pertama kalinya, tribunal dan pengadilan-pengadilan yang menyusulnya secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab untuk kekejaman bisa dibebankan kepada individu menurut hukum internasional: “Semua orang yang melakukan 8 tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggung-jawab dan dengan demikian mendapat hukuman”.18 Lebih lanjut lagi, dengan menolak pembelaan tradisional tentang tanggung jawab individu terhadap kekejaman, Nuremberg secara dramatis memperluas potensi pertanggungjawaban individual untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan negara. Sementara, secara tradisional, kepala negara memiliki imunitas sebagai pemegang kedaulatan menurut Prinsip Nuremberg, para pejabat publik tidak bisa melakukan pembelaan serupa berdasarkan posisi jabatan mereka, namun tetap harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana mereka.19 Meskipun menurut aturan militer tradisional dalam struktur komando, “ketaatan pada perintah” merupakan pembelaan, menurut Prinsip Nuremberg, orang yang melakukan tindakan berdasarkan perintah dapat dituntut pertanggungjawabannya.20 Dengan menghilangkan pembelaan “tindakan negara” dan “perintah atasan”, Prinsip Nuremberg memberikan kejelasan pada kaburnya pertanggungjawaban yang merupakan ciri kejahatan yang dilakukan di bawah rezim totaliter. Di bawah hukum perang, prinsip pertanggungjawaban komando memberikan dasar untuk pembebanan tanggung jawab terhadap atasan untuk pelanggaran bawahan. Dasar ini diperkuat oleh Prinsip Nuremberg yang mencabut pembelaan imunitas dari kepala-kepala negara. Titik ekstrem dalam pengadilan berdasar status setelah Nuremberg tergambar dalam pengadilan kejahatan perang Tokyo untuk kekejaman yang dilakukan di Filipina, di mana prinsip pertanggungjawaban komando diterapkan secara luas. Dalam pengadilan Tokyo, Jenderal Tomoyui Yamashita dianggap bertanggung-jawab atas tindakan kekejaman yang dilakukan pasukannya, dijatuhi vonis dan dieksekusi – semuanya tanpa bukti keterlibatan personal atau bahkan pengetahuan terhadap tindakan yang dilakukan bawahannya. Namun, pengadilan yang membahas kasusnya menganggap bahwa “ia seharusnya mengetahui” pelanggaran hukum perang yang dilakukan di wilayah komandonya.21 Dari titik pandang sejarah, standar kelalaian untuk pertanggungjawaban komando dalam kasus Yamashita menjadi sui generis, suatu titik ekstrem dalam konsepsi pertanggungjawaban atasan untuk 18 PBB, Sidang Umum, International Law Commission: Report on the Principles of the Nuremberg Tribunal, Prinsip I, A/1316 (1950). 19 Ibid. Prinsip III dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seorang pelaku tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau pejabat pemerintahan yang bertanggung-jawab tidak melepaskannya dari tanggung jawab menurut hukum internasional.” 20 Baik Nuremberg maupun kasus lain sesudahnya, kasus Einsatzgruppen, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. 4-5 (Washington, DC: GPO, 19491953), menolak pembelaan kepatuhan pada perintah dan doktrin respondeat superior yang mengalihkan tanggung jawab pada pemberi perintah. Doktrin “tanggung jawab absolut” sebaliknya, yang menyatakan bahwa perintah atasan tidak pernah bisa menjadi justifikasi tindakan melanggar hukum, diajukan dalam Mitchell v.Harmony, 13 How 115 (1851) dan kemudian dimuat dalam Prinsip Nuremberg pada Pasal 8. Dalam standar ilegalitas yang diterima, jika seseorang yang bisa berpikir dengan baik bisa memahami bahwa perintah yang diterimanya secara manifes ilegal, maka pembelaan kepatuhan ini ditolak. Prinsip IV dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seseorang bertindak mengikuti perintah pemerintahnya atau atasannya tidak membebaskannya dari tanggung jawab menurut hukum internasional, dengan syarat bahwa ia bisa melakukan pilihan moral.” 21 Lihat Judgment in the Tokyo War Crimes Trial, 1948, dicetak ulang sebagian dalam Richard Falk, Gabriel Kolko dan Robert Jay Lifton (eds.), Crimes of War: A Legal, Political-Documentary, and Psychological Inquiry into the Responsibility of Leaders, Citizens, and Soldiers for Criminal Acts in Wars, New York: Ramdon House, 1971, 113. Jenderal Yamashita mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang mengafirmasi prinsip tersebut. Lihat In re Yamashita, 327 US I, 13-18 (1945). 9 kekejaman yang dilakukan bawahannya. Dalam pengadilan High Command dan Hostage terhadap perwira tinggi Angkatan Darat Jerman, standar Yamashita ini ditolak, dan pengadilan mewajibkan adanya pengetahuan dan partisipasi individual atau persetujuan terhadap tindakan pidana, atau kelalaian pidana: “Tidak semua individu dalam struktur komando terkait dengan tindakan kejahatan itu..... Pasti terdapat kesalahan pribadi.”22 Vietnam membangkitkan kembali perhatian ilmiah tentang masalah tanggung jawab pimpinan terhadap kejahatan negara yang berat, dan menjadikan amat jelas tingginya unsur politis yang terlibat dalam penggunaan secara permisif prinsip tanggung jawab komando.23 Kasus tentang kekejaman Mylai mengarah pada penyempitan prinsip tanggung jawab komando. Harus terdapat kaitan antara kekejaman yang terjadi di wilayah yang merupakan daerah kendali komandan tersebut dan adanya kesalahan pribadi di sisi komandan tersebut.24 Versi prinsip pertanggungjawaban komando yang demikian inilah yang kini dijunjung dalam konvensi hukum internasional: kelalaian untuk mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran menjadi salah satu syarat. Secara eksplisit menolak standar “ia seharusnya mengetahui” dari Yamashita, dalam Pasal 86 dari Konvensi Genewa pasca-perang, “pengetahuan” memberikan kewajiban untuk mengambil “semua tindakan yang dimungkinkan” untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran.25 Hukum kemanusiaan internasional memberikan kerangka kerja dan bahasa normatif untuk berpikir tentang keadilan suksesor.26 Kesalahan rezim bisa dikonseptualkan dan diakomodasi oleh hukum perang. Jadi, prinsip pertanggungjawaban individual di Nuremberg adalah prinsip yang kompleks, yang tampak dari evolusi prinsip tanggung jawab komando, juga dalam cara prinsip tersebut memediasi pertanggungjawaban individu dan kolektif, seperti hukum konspirasi, yang memungkinkan pengadilan terhadap individu karena keanggotaan dalam kelompok tertentu.27 Namun, sukar untuk menyesuaikan hukum internasional dan analogi militernya untuk mencantumkan seluruh isu keadilan suksesor. Paradigma internasional menekankan pendekatan berdasar status bagi peradilan pidana suksesor, yang umumnya mengaitkan status politik individual dengan konteks di dalam rezim. Namun standar pertanggungjawaban yang luas, seperti dalam kasus Yamashita, menunjukkan bahwa membebankan tanggung jawab kepada komandan atas tindakan bawahan mereka dapat memberikan hasil yang buruk. Bila penuntutan didasarkan pada jabatan resmi sebagai dasar tanggung jawab pidana, hal ini mengancam prinsip tanggung jawab individual. 22 United States v. Wilhelm von Leeb, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 462 (1950) (High Command Case); United Sates v. Wilhelm List, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 1230 (1950) (Hostage Case). 23 Lihat umumnya Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, Chicago: Quadrangle Books, 1970. Lihat juga Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 177-415. 24 Lihat United States v. Calley, 46 CMR 1131 (1973). Lihat juga Gary Kamarow, “Individual Responsibility under International Law: The Nuremberg Principles in Domestic Legal System”, International and Comparative Law Quarterly 29 (1980): 26-27, untuk diskusi singkat tentang kasus Calley dalam konteks ini. 25 Protokol I, “Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts”, 8 Juni 1977, Treaties and International Agreements Registered or Filed of Reported with the Secretariat of the United Nations 1125, No. 17512 (1979): 609. 26 Untuk diskusi ilmiah, lihat Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford: Clarendon Press, 1998. 27 Lihat Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, New York: Knopf 1992. 10 Setelah Nuremberg, pemahaman kita tentang penuntutan pertanggungjawaban oleh rezim suksesor tidak pernah sama dengan sebelumnya. Prinsip-prinsip Nuremberg memberikan perluasan potensi pertanggungjawaban pidana individual – di kedua sisi hierarki pemegang kekuasaan. Jurisprudensi pasca-perang menandakan ekspansi mendasar tentang potensi pertanggungjawaban pidana individual tanpa batas yang kaku. Ketiadaan batasan ini bahkan diakui waktu itu. Sementara pengadilan dimulai dengan para penjahat perang utama, tidak ada tulisan dalam Piagam Nuremberg yang membatasi pembebanan pertanggungjawaban hanya kepada pejabat-pejabat tinggi Nazi. Sebaliknya, piagam tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menuntut pertanggungjawaban para pemimpin barulah titik awal, dan masih akan ada pengadilan-pengadilan yang menyusul.28 Dalam transformasi pasca-perang tentang pemahaman tanggung jawab individual terhadap kejahatan berat negara, timbullah dilema berikut ini: di satu sisi prinsip-prinsip yang disusun di Nuremberg secara mendasar memperluas potensi tanggung jawab pidana individual, namun di sisi lain prinsip-prinsip tersebut tidak memberikan dasar untuk menentukan, dari semua yang berpotensi bertanggungjawab, siapa yang harus diadili. Ledakan masalah pertanggungjawaban pasca-Nuremberg ini memiliki dampak besar yang belum semuanya terselesaikan. Bagi para analis politik dan ilmuwan hukum, Nuremberg dianggap menimbulkan perubahan besar dalam pemahaman tentang tanggung jawab pidana individual menurut hukum internasional, tetapi masih belum ada bayangan tentang bagaimana perubahan tersebut menimbulkan dilema pertanggungjawaban. Ekspansi masalah pertanggungjawaban kontemporer ini menimbulkan masalah besar bagi rezim penerus yang sedang mempertimbangkan siapa yang akan mereka adili, dan untuk kejahatan apa. Bahkan, masalah ini menjadi perdebatan ilmiah yang berkisar pada penghukuman di masa transisi,29 dengan alasan yang melampaui ciri-ciri khusus konteks politik transisi suatu begara, dan merujuk pada perkembangan kontemporer dalam konseptualisasi pertanggungjawaban hukum. Prinsip panduan yang bisa dipergunakan dalam hal ini hanyalah proporsionalitas. Prioritasnya adalah untuk mengadili mereka yang “paling bertanggung-jawab untuk kejahatan yang paling parah”, dimulai dengan mereka yang berada pada tingkat pertanggungjawaban yang paling tinggi terhadap kejahatan yang paling mengerikan.30 Namun, seperti akan dibicarakan lebih lanjut di bawah, proporsionalitas dalam tingkat abstrak belum bisa menyelesaikan dilema yang timbul dari usaha untuk merespon kejahatan berskala besar yang dilakukan oleh rezim represif, dengan menggunakan hukum pidana. Bahkan, seperti ditunjukkan praktik transisional di bawah, prioritas untuk memberikan hukuman bukanlah pemikiran yang universal, namun tergantung pada kondisi politik yang khas dari suatu masyarakat, dan juga jangkauan pergeseran normatifnya. Penerapan Preseden Nuremberg di Pengadilan Nasional 28 Ibid. Seperti Jaime Malamud-Goti, Game without End: State Terror and the Politics of Justice, Norman: University of Oklahoma, Press. 30 Helsinki Watch, War Crimes in Bosnia Hercegovina, Vol. I, New York: Human Rights Watch, 1992. (Laporan Helsinki Rights Watch). 29 11 Meskipun penggunaan prinsip pertanggungjawaban militer bisa diterima dalam konteks pascaperang, dan transisi sering kali terjadi menyusul masa peperangan, namun transisi juga bisa terjadi dengan cara-cara lain, dan standar Nuremberg tidak selalu dapat memandu keadilan suksesor ini. Namun, kerangka kerja peradilan pidana internasional memiliki daya tarik yang melampaui pengadilan-pengadilan pasca-perang, ke model-model lain keadilan suksesor. Keadilan transisional berkaitan dengan analogi perang dan damai, dan demikian juga hukum kemanusiaan internasional dan hukum domestik. Analogi militer ini tampak jelas bila kebijakan pengadilan suksesor diawali dengan pengadilan terhadap pimpinan rezim terdahulu. Memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap status politik merupakan perkembangan logis dari analogi kejahatan perang ke pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan kediktatoran dan represif. Pandangan umum yang berlaku adalah bahwa setelah pemerintahan non-demokratik, mungkin adil untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pemimpin tertinggi politik, namun keadilan transisional yang didasarkan pada paradigma hukum internasional yang luar biasa dan hukum perang tampaknya bertentangan dengan pandangan umum tentang peradilan pidana. Timbul pertanyaan tentang apakah pertanggungjawaban untuk kesalahan yang dilakukan pada masa rezim represif bisa dengan adil dibebankan kepada para pemimpin politik tertinggi suatu negara. Sejauh mana kekuasaan politik dipegang oleh diktator, atau keberadaan rezim represif menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana? Mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada dasar jabatan resmi pelanggar akan bertentangan dengan pandangan umum tentang berlakunya hukum pidana di negara-negara demokrasi dan memberikan tantangan bagi kedaulatan hukum. Pengadilan suksesor sebenarnya jarang didasarkan pada hukum perang dan hukum internasional. Transisi Amerika Latin dari pemerintahan militer adalah contoh kontemporer yang unik. Di Argentina, kekalahan dalam Perang Malvinas menyebabkan keruntuhan angkatan bersenjata dan memungkinkan transisi dari junta militer ke demokrasi, yang berpuncak pada pengadilan terhadap para pemimpin junta untuk “kelalaian berat” dalam menjalankan peperangan.31 Contoh kontemporer lainnya, setelah keruntuhan Soviet, transisi di wilayah tersebut dibayangi oleh suatu perasaan tentang pendudukan, analog dengan kekalahan pasca-perang. Jadi revolusi di Hungaria dan bekas Cekoslowakia berawal dengan peringatan perlawanan terhadap invasi Nazi dan Soviet. Timbul pertanyaan kritis tentang keadilan transisional di wilayah tersebut: Kediktatoran siapa? Keadilan siapa? Setelah keruntuhan komunis, pertanyaan mendasar keadilan suksesor adalah sejauh mana represi dapat dipandang dalam kerangka paradigma pasca-perang yang lazim – yaitu sebagai penjajah asing. Pada akhirnya, pertanyaan tersebut mengalihkan tanggung jawab nasional ke tingkat individual. Demikianlah, maka para pemimpin terdahulu dianggap bertanggung-jawab karena mereka berkolaborasi dengan invasi Soviet ke negara-negara mereka. Pengadilan suksesor disusun pada titik balik yang penting, menarik garis antara kebebasan dan represi, perlawanan dan kolaborasi. Ini adalah garis yang sedang ditarik dan akan ditarik kembali dalam pengadilan-pengadilan di wilayah ini. Titik balik yang penting di bekas Cekoslowakia adalah tahun 1968. Pada gelombang pertama pengadilan setelah revolusi, para mantan pemimpin partai diadili dengan tuduhan pengkhianatan dan kolaborasi, dalam kerangka penyalahgunaan kekuasaan publik dalam 31 Proceedings of Las Malvinas Trial (arsip penulis). 12 represi terhadap pemberontakan Praha.32 Empat tahun kemudian, sebuah hukum baru yang menyatakan komunisme “melanggar hukum” dan “tidak sah” memberikan dasar untuk pengadilan lebih lanjut.33 Hukum tersebut menyatakan “menggabungkan kekuatan dengan kekuatan asing” seperti membantu membantu pendudukan negeri itu pada tahun 1968 sebagai pelanggaran. Jadi, mantan sekretaris Komite Sentral Partai Komunis, Vasil Bilák, dituduh melakukan pengkhianatan karena mengundang angkatan bersenjata negara-negara Pakta Warsawa ke Cekoslowakia pada tahun 1968. Namun, pada akhirnya, pengadilan tersebut hanya sampai pada tahap penyidikan terhadap sejarah.34 Di Polandia, pertanyaan yang dominan dalam penyelidikan komisi parlementer terhadap mantan pemimpin negeri tersebut, Jenderal Wojciech Jeruzelski,35 adalah apakah penerapan hukum perang pada tahun 1981 untuk menghancurkan gerakan Solidaritas adalah akibat dari tekanan Soviet atau memang karena kolaborasi dari pemerintah Polandia. Jika keputusan Jeruzelski untuk menerapkan hukum perang merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah asing, hal tersebut bisa menjadi dasar untuk tuduhan pengkhianatan.36 Pengadilan lainnya dijalankan terhadap “kejahatan-kejahatan perang”, dianalogikan terhadap hukum internasional. Peradilan suksesor di Hungaria secara formal didasarkan pada pengkhianatan yang didefinisikan sebagai kolaborasi dengan Soviet, dan terutama, dalam represi berdarah terhadap pemberontakan 1956.37 Tinjauan konstitusional terhadap hukum tentang pengkhianatan di Hungaria menyelesaikan masalah dilema yang ditimbulkan dari penggunaan hukum pidana untuk mengutuk hal-hal yang semula didukung oleh rezim sebelumnya. Ketika pengadilan konstitusional Hungaria menganggap hukum baru tentang pengkhianatan itu inkonstitusional karena retroaktivitas,38 sebuah hukum baru yang membatasi pelanggaran yang bisa diadili hanyalah “kejahatan perang”,39 memungkinkan proses pengadilan untuk berjalan berdasarkan 32 Lihat “Four Hardline Communists Investigated over 1968 Prague Invasion”, Reuters, 17 April 1990, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters; “August 1968 – Gateway to Power for Number of Politicians”, CTK National News Wire, 18 Agustus 1998, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK. 33 Act on the Illegality of the Communist Regime and Resistance to It, Act. No. 198/1993 (Republik Ceko, 1993). 34 Lihat “Velvet Justice for Traitors Who Crushed 1968 Prague Spring”, The Telegraph, Praha 23 Agustus 1998 (melaporkan ketiadaan sanksi bahkan setelah penyidikan delapan tahun). 35 Lihat “Polish Politicians Ask for Trial for Martial Law Instigators”, Reuters, 9 Desember 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga Tadiusz Olszaski, “Communism’s Last Rulers: Fury and Fate”, Warsaw Voice, 18 November 1992, tersedia di Lexis, News Library. Untuk kisah pengakuan Jeruzelski dan lainlainnya, lihat RFE/RL Daily Report No. 49, 12 Maret 1993. Lihat juga “Walesa to Testify on Martial Law”, Polish News Bulletin, 25 Mei 1994, bagian politik. 36 Hingga terbitnya buku ini, Jeruzelski belum diadili karena alasan kesehatan. Lihat “Jeruzelski Will Not Be Tried”, Polish News Bulletin, 9 Juli 1997, bagian politik. Namun, terungkapnya dokumen-dokumen yang memberatkan mungkin akan memperkuat posisi pihak-pihak yang menginginkan pengadilan. Lihat “Constitutional Accountability Commision Meets”, Polish News Bulletin, 26 Oktober 1994; “Russian Dissident Accuses Jeruzelski”, Polish News Bulletin, 20 Mei 1998, bagian politik. Lihat juga Tad Szulc, “Unpleasant Truths about Eastern Europe”, Carnegie Endowment for International Peace, Foreign Policy, 22 Maret 1996, tersedia di Lexis, News Library. 37 Lihat Michael Shields, “Hungary Gets Ready to Try to Communist Villains of 1956”, Reuters, 5 November 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga Jane Perlez, “Hungarian Arrests Set off Debate: Should ’56 Oppressors be Punished?” New York Times, 3 April 1994, tersedia di Lexis, News Library. 38 Constitutional Court Decision on the Statute of Limitation, No. 2086/A/1991/14 (Hungaria, 1992). 39 Act on Procedures Concerning Certain Crimes Committed during the 1956 Revolution (Hungaria, 1993) (arsip Center for the Study of Constitutionalism in Eastern and Central Europe, University of Chicago). Pada tanggal 3 November 1993, diperintahkan penyelidikan terhadap pembantaian 1956, “atas kecurigaan adanya kejahatan 13 analogi pada pengadilan-pengadilan pasca-perang. Ketika para pemimpin partai komunis Rumania diadili dalam pengadilan yang sebenarnya tidak memenuhi prinsip kedaulatan hukum, tuduhan yang dialamatkan kepada mereka adalah kejahatan perang menurut hukum internasional. “Genosida” dituduhkan di pengadilan-pengadilan militer terhadap para pemimpin utama yang menindas gerakan rakyat pada tahun 1989, meskipun pada akhirnya tuntutan yang diberikan lebih ringan. Tuduhan “kejahatan terhadap kemanusiaan” juga dialamatkan kepada mantan pejabat komunis di Albania pada masa transisi. Suatu usaha bersama sedang berjalan untuk memperluas dan menormalkan pemahaman pasca-perang tentang penindasan negara. Usaha ini tampak, misalnya, dalam perkembangan hukum kemanusiaan internasional, di mana pemahaman tentang pelanggaran berupa penindasan di masa perang diperluas hingga melampaui respon-respon internasional menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam batasan negara.40 Hal ini juga terlihat dalam jurisdiksi tribunal kejahatan perang internasional ad hoc di bekas Yugoslavia, demikian pula dalam jurisdiksi rencana pengadilan pidana internasional. Dalam contoh-contoh kontemporer tersebut, suatu pemahaman dinamis tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” bergerak dari semula hanya terbatas pada konflik bersenjata hingga menjadi sinonim dengan penindasan.41 terhadap kemanusiaan”. Sejak disahkannya hukum tersebut, penangkapan, pengadilan dan penuntutan telah berjalan. Lihat “Court Convicts Defendant for War Crimes in 1956 Uprising”, BBC Summary of World Broadcasts, 18 Januari 1997, tersedia di Lexis, News Library. Lihat juga “Hungary Arrests More in 1956 Shootings Probe”, Reuters, 11 Februari 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 40 Lihat misalnya “United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects”, 10 Oktober 1980, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 1342, No. 22495 (1983): 137; Protokol I, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 Agustus 1949, Treaties and International Agreements Registered of Filed of Reported with the Secretariat of the United Nations 75, No. 973 (1950): 287. Untuk analisis mendalam, lihat Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, New York: Oxford University Press, 1989 (menjelaskan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik internasional dan internal). 41 Lihat Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. doc. A/Conf. 183/9. 17 Juli 1998, Pasal 7 (mendefinisikan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai bagian dari “kekerasan yang luas atau sistematis yang diarahkan kepada kelompok penduduk sipil apa pun”). Untuk ilustrasi, lihat umumnya Helsinki Watch, War Crimes in Bosnia-Hercegovina (melaporkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Balkan). Lihat Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Pasal 5, dilampirkan pada PBB, Sidang Umum, Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the U.N. Security Council Resolution 808, S/25704 (1993), dicetak ulang dalam International Legal Materials 32 (1993): 1159, 1193-97. Berbagai tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, penindasan atas dasar politik, ras dan agama, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya”. Pemahaman Komisi Pakar adalah bahwa Tribunal Internasional memiliki jurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lihat PBB, Dewan Keamanan, Final Report of the Commission of Expert Established Pursuant to Security Council Resolution 780, S/1994/674 (1992), 13. Lihat juga Prosecutor v. Tadic, kasus No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 2 Oktober 1995), dicetak ulang dalam International Legal Materials 35 (1996): 32. Namun, sidang banding memberikan batasan terhadap interpretasi “pelanggaran berat” dan menekankan bahwa pelanggaran demikian yang merupakan jurisdiksi haruslah merupakan bagian dari konflik bersenjata internasional. Jurisdiksi tribunal mencakup kejahatan yang dilakukan bukan oleh agen negara, selama dilakukan “dengan pengaruh” negara. Statuta tribunal ini dimuat dalam PBB, Dewan Keamanan, Report of the SecretaryGeneral Pursuant to Paragraph 2 of U.N. Security Council Resolution 808, (1993), dicetak ulang dalam International Legal Materials 32 (1993): 1159. Pasal 2 tentang kompetensi Tribunal Internasional menyatakan: 14 Keunggulan hukum internasional dalam menciptakan pertanggungjawaban pidana, terutama hukum pidana internasional yang digabungkan dalam kemajuan-kemajuan pascaperang, telah menjadikan hukum pidana internasional menjadi bahasa dominan dalam keadilan suksesor. Meskipun kekuatannya tidak tampak dalam pengadilan-pengadilan internasional, kekuatan normatifnya yang besar tampak dalam pemahaman yang meluas bahwa penindasan oleh negara melampaui batasan hukum domestik dan memiliki pertanggungjawaban internasional. Pengakuan tentang nilai-nilai umum ini menimbulkan semacam bentuk pertanggungjawaban, dengan identifikasi dan pengungkapan adanya penindasan tanpa memperhatikan batas negara.42 Bila suatu negara gagal melindungi warganya dari penindasan, respon utama dari komunitas hak asasi manusia internasional adalah dengan mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran berat. Pada tahun-tahun belakangan ini, terdapat perkembangan penting dengan menguatnya mekanisme internasional yang dirancang untuk menyelidiki dan mempublikasikan klaim kekejaman. Pertanggungjawaban terhadap komunitas dunia muncul terutama dari pengungkapan secara terbuka keberadaan penindasan di suatu negara. Jadi, jika dan ketika ia dibentuk, peran tribunal pidana internasional yang permanen mungkin akan menjadi sebagai badan penyelidikan dan pengaju tuduhan. Warisan terpenting dari preseden Nuremberg adalah bahwa masalah pertanggungjawaban negara tidak akan lagi dibatasi oleh batas negara, namun menjadi masalah tingkat internasional. Keadilan Transisional dan Tatanan Hukum Nasional dalam Perspektif Komparatif Meskipun skema internasional memiliki banyak daya tarik, pada umumnya rezim-rezim dalam transisi berusaha untuk menormalkan proses pengalihan kekuasaan dengan mengintegrasikan respon mereka dalam sistem hukum yang sudah ada. Pertanyaannya menjadi bagaimana keadilan suksesor bisa menjelaskan perubahan rezim politik, dan terutama, bagaimana mengakomodasi ciri utama transisi, yaitu pergeseran normatif yang ditimbulkan oleh perubahan rezim politik. Respon transisional dalam hukum nasional memiliki watak beragam dalam kemampuannya untuk mengakomodasi transformasi politik, karena proses juridis tersebut dijalankan dalam legalitas yang berlaku. Sering kali, usaha untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku pelanggaran di masa rezim pendahulu dapat menekan sistem hukum domestik hingga ke batas-batasnya. Respon-respon terhadap kekerasan politik yang luar biasa menguji prinsip-prinsip utama kedaulatan hukum yaitu keamanan dan keberlakuan hukum secara umum. Sejumlah pengadilan nasional mengikuti gelombang transisi politik. Sebelum Perang Dunia Pertama, terdapat pengadilan untuk kekejaman yang dilakukan terhadap warga Armenia “Tribunal internasional memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvnsi Jenewa 12 Agustus 1949”. Pasal tersebut kemudian memberikan rincian pelanggaran. Pasal 7 mendefinisikan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai bagian dari “kekerasan yang luas atau sistematis yang diarahkan kepada kelompok penduduk sipil apa pun”. 42 Sebagai contoh, Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di Yugoslavia nyaris sejak dimulainya konflik, menerbitkan catatan yang mendetail dan menyerukan pengadilan terhadap kejahatan perang. Lihat Helsinki, War Crimes in Bosnia-Hercegovina, Vol.1 dan 2. 15 di wilayah Kesultanan Ottoman.43 Setelah Perang Dunia Pertama, kesepakatan di Versailles memungkinkan Jerman untuk melakukan pengadilan nasionalnya sendiri; namun pada akhirnya jumlahnya amat terbatas. Setelah Perang Dunia Kedua, tindakan para Nazi dan kolaborator mereka menimbulkan usaha keras untuk menuntut pertanggungjawaban. Meskipun terdapat dominasi paradigma internasional dalam literatur ilmiah, respon legal terhadap Nazi dan kolaboratornya pada umumnya bersifat domestik. Pengadilan terhadap mereka yang terlibat dalam kekejaman selama Perang Dunia Kedua masih menjadi penyusun utama preseden pertanggungjawaban pidana pada tingkat nasional. Pengadilan-pengadilan nasional tersebut berlangsung selama hampir lima dekade, dengan sistem-sistem hukum Common Law, sipil dan sosialis, dan berlangsung di hampir semua negara tempat terjadinya kejahatan tersebut dan di negara lainnya.44 Terlebih lagi, di seluruh Eropa, dampak hukum domestik dari transisi pasca-perang masih terasa. Di Jerman, kasus yang terkait dengan Perang Dunia Kedua masih berkangsung dari dekade 1950-an hingga kini.45 Di Prancis, pengadilan Klaus Barbie pada akhir dekade 1980-an masih diikuti kasus lain yang diajukan terhadap kolaborator tingkat tinggi, seperti Paul Touvier dan Maurice Papon.46 Belanda terus mengadili para kolaboratornya. Australia dan Kanada melakukan pengadilan terhadap kolaborator Perang Dunia Kedua yang tinggal di wilayahnya pada akhir dekade 1980-an.47 Di Inggris, War Crimes Act 1991 disahkan untuk memungkinkan pengadilan terhadap tersangka kolaborator pada masa perang yang tinggal di wilayah tersebut. 43 Lihat umumnya Arnold J. Toynbee, Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, New York: Tankian, 1975. Lihat juga Dickran Boyajian, Armenia: The Case for a Forgotten Genocide, Wesrwood, N.J: Educational Book Crafters, 1972. 44 Lihat Symposium, “1945-1995 Critical Perspectives of the Nuremberg Trials and State Acountability”, New York Law School Journal of Human Rights 12 (1995): 453; Inge S. Neumann, European War Crimes Trials, ed., Robert A. Rosenbaum, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1951. Lihat umumnya Randolph L. Braham (ed.), Genocide and Retribution, Boston: Kluwer-Nijhoff, 1983. Untuk daftar bibliografi lengkap, lihat umumnya Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals, and War Crimes Trials; Neumann, European War Crimes Trials. Lihat juga Owen M. Kupferschmid Holocaust and Human Rights Project Seventh International Conference, “Judgements on Nuremberg: The Past Half Century and Beyond – A Pannel Discussion of Nuremberg Prosecutors”, Boston College Third World Law Journal 16 (1996): 1993; Symposium, “Holocaust and Human Rights Law: The Fourth International Conference”, Boston College Third World Law Journal 12 (1992): 1. 45 Lihat Adalbert Rückerl, The Investigation of Nazi Crimes: 1945-1978: A Documentation, terjemahan Derek Rutter (Heidelberg, Karlsruhe4: C.F. Müller, 1979). Lihat “5,570 Cases of Suspected Nazi Crimes Remain Open,” This Week in Germany, 3 Mei 1996 (melaporkan bahwa 106.178 orang telah diadili dan 6.494 diputuskan hukumannya). 46 Mengenai pengadilan Klaus Narbie, lihat misalnya, Féderation Nationale des Déportés es Internés Réesitstant et Patriotes v. Barbie, 78 ILR 125 (Fr. Cass. Crim., 1985). Pengadilan Paul Touvier untuk kejahatan terhadap kemanusiaan diakhiri dengan hukuman seumur hidup. Lihat Alam Riding, “Frenchman Convicted of Crimes against the Jews in ’44,” New York Times, 20 April 1994, Sec. A3; Judgment of Apr. 20, 1994, Cour d’assises des Yvelines. Maurice Papon, dalam usia 87 tahun, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas perannya dalam deportasi warga Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Tuduhan lain tentang kejahatan terhadap kemanusiaan diajukan kepada Jean Leguay dan Rene Bousquet, namun keduanya meninggal dunia selama proses berjalan. Judgment of Oct. 21, 1982, Cass. Crim. Lihat Bernard Lambert, Bousquet, Papon, Touvier, Inculpés de Crimes contre I’humanite: Dossiers d’accusation (Paris: Federation Nationale des Déportés es Internés Résistants et Patriotes). 47 Lihat Timothy L.H. McCormack dan Jerry J. Simpsons, “The International Law Commission’s Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind: An Appraisal of the Substantive Provisions”, Criminal Law Forum 4 (1994): 1; Ronnie Edelman et al., “Prosecuting World War II Prosecutors: Efforts at an Era’s End”, Boston College Third World Law Journal 12 (1992): 199. 16 Dalam gelombang transisi kedua di abad ke-20, di Eropa Selatan, terdapat pengadilan suksesor terhadap junta Yunani dan Portugal.48 Pada gelombang ketiga transisi politik di Amerika Latin dan Afrika, Argentina mengadili para komandan dan perwira militernya; dan di Republik Afrika Tengah, “kaisar” tiran Jean-Bedel Bokassa diajukan ke Pengadilan. Pada transisi dari pemerintahan komunis, terdapat beberapa pengadilan terhadap para pimpinan tingkat tinggi di Rumania dan Bulgaria, dan di bekas Cekoslowakia, pengadilan terhadap pejabat partai tingkat tinggi dan menengah. Di Jerman, terdapat pengadilan terhadap semua tingkat, yang umumnya terkait pada penembakan-penembakan di Tembok Berlin.49 Keruntuhan Yugoslavia mendorong konflik dan kekejaman Bosnia dan diikuti oleh proses pengadilan. Setelah runtuhnya rezim Marxis, Etiophia mengadili jajaran tertinggi rezim pendahulunya.50 Sejak transisi politiknya, Rwanda melakukan pengadilan genosida.51 Kejahatan Negara, tetapi Peradilan Individual Peradilan pidana transisional menimbulkan dilema penerapan prinsip tanggung jawab individual terhadap kejahatan berat yang dilakukan pada masa pemerintahan non-liberal. Setelah represi, masalah utamanya adalah bahwa negara harus merespon kesalahan yang dilakukan rezim pendahulunya dan menuntut pertanggungjawaban. Bagaimana cara negara bisa memediasi pergeseran normatif antara rezim dalam kondisi yang penuh paradoks dan terkompromi, di mana terdapat keterlibatan negara dalam kejahatan di masa lalu? Dalam kondisi demikian, apa kaitan antara tanggung jawab individu dan negara? Dalam pergeseran setelah pemerintahan represif, luasnya penindasan pada masyarakat non-demokratik sering kali menyebabkan kesulitan dalam usaha untuk menemukan keadilan. Pertanyaan penting yang timbul dalam penentuan tanggung jawab pidana adalah: Siapa yang diberikan prioritas? Apakah para pemimpin politik yang merupakan otak di belakang penindasan, atau mereka yang di bawah yang secara langsung melakukan tindakan brutal tersebut? Apakah sebaiknya kebijakan pengadilan suksesor mengadili semua pelaku pelanggaran, atau apakah pengadilan yang selektif dapat dianggap adil? Dan, jika pengadilan dilakukan secara selektif, atas dasar apa kebijakan tersebut bisa diterima? 48 Untuk pembicaraan tentang pengadilan Yunani, lihat Nikiforos Diamandouros, “Regime Change and the Prospects of Democracy in Greece: 1974-1983, dalam Guillermo O’Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perpectives, Baltimore: Johns Hpokins University Press, 1991, 138. Untuk pembicaraan tentang transisi Portugal, lihat Kenneth Maxwel, “Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal”, dalam Guillermo O’Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991, 109-37. Lihat juga John H. Herz (eds.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Wesport: Conn: Greenwood Press, 1982. 49 Lihat misalnya Border Guards Prosecution Case, International Law Reports 100 (1995): 366, 30. Untuk pembicaraan tentang beberapa dari kasus tersebut, lihat Stephan Hobe dan Christian Tietje, “Government Criminality: The Judgment of the German Federal Constitutional Court of 14 October 1996”, German Yearbook of International Law 39 (1996): 523. Untuk tinjauan jurnalistik komparatif tentang berbagai respon di wilayah tersebut, lihat Tina Rosenberg, The Hounted Land, New York: Random House, 1996. 50 Lihat “Symposium, 1945-1995 Critical Perspectives on the Nuremberg Trials and State Accountability,” New York Law Shool Journal of Human Rifhts 12 (1995): 453 (tinjauan tentang pengadilan Etiophia). 51 Lihat “Trial of 51 on Rwanda Genocide Charges Opens in Byumba”, Agence France-Presse (Kigali), 18 Maret 1998. Lihat juga Payam Alchavan, “The International Criminal Court Tribunal For Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment”, American Journal of International Law 90 (1996): 501. 17 Di mana seharusnya kebijakan pengadilan bermula? Klaim normatif bahwa pemberian hukuman akan mendorong kedaulatan hukum tidak dengan sendirinya menjustifikasi menghukum semua pelaku pelanggaran. Bahkan, sasaran untuk membela demokrasi dan memperkuat kedaulatan hukum dapat dicapai dengan sejumlah penuntutan yang berfungsi sebagai contoh. Dalam praktiknya, akan terlihat bahwa selektivitas hingga titik tertentu tidak dapat dihindarkan. Selektivitas itu didasarkan pada pertimbangan atas jumlah besar orang yang terlibat dalam penindasan dalam sebuah negara modern, kekurangan sumber daya yudisial dalam masyarakat transisional, dan tingginya biaya politik dan biaya-biaya lain dari pengadilan suksesor. Dengan batasan-batasan demikian, pengadilan selektif atau “percontohan”, tampaknya dapat memberikan suatu rasa keadilan.52 Namun batasannya amat tipis. Suatu kebijakan pengadilan percontohan akan menimbulkan risiko melemahnya tujuan demokratis dari pengadilan tersebut, dan malah memberikan kesan keadilan politis. Kebijakan pengadilan selektif dapat mengancam kedaulatan hukum. Siapa yang paling perlu dimintai pertanggungjawabananya atas kekerasan dalam masyarakat yang tertindas? Bagaimana pertanggungjawaban pidana bisa dibagikan kepada mereka yang memberikan perintah dan mereka yang melaksanakan perintah? Prinsip apa yang bisa digunakan untuk melakukan hal ini? Pada umumnya, anggapan kita tentang tanggung jawab pidana adalah bahwa mesti ada suatu kesalahan, kaitan antara kerugian di satu pihak dan kesalahan individual di pihak lainnya.53 Namun, intuisi kita tentang tanggung jawab pidana tidak tepat dipergunakan untuk memahami dilema transisional yang khas. Pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam konteks pemerintahan yang represif memberikan implikasi tentang keberadaan pelanggaran sistemik, tanggung jawab pemerintah, seperti pelanggaran tugas khusus, tanggung jawab para pejabat terhadap bawahannya, dan secara lebih mendasar, tugas utama negara untuk melindungi warganya.54 Secara historis, mereka yang dianggap paling bertanggung-jawab untuk kesalahan di masa lalu adalah para pemimpin politik tertinggi. Pengadilan suksesor kontemporer menunjukkan kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin politik terhadap pelanggaran-pelanggaran terberat dalam pemerintahan yang represif. Maka, dalam pengadilan suksesor setelah runtuhnya komunis, usaha untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin politik berarti mengadili pelanggaran yang dilakukan tepat pada awal pemerintahan yang represif, atau menjelang akhir kekuasaan rezim tersebut. Kembali ke pelanggaran yang dilakukan pada saat pengambilalihan kekuasaan oleh komunis berarti mundur ke setengah abad yang lalu. Mengadili kejahatan yang telah berlangsung lama menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan jurisdiksi dan berisiko menimbulkan ketidaktaatan pada prosedur yang 52 Untuk argumen mendukung pengadilan selektif, lihat Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rughts Violations of a Prior Regime”, Yale Law Journal 100 (1991): 2537. Lihat juga Guillermo O’Donnel dan Phillipe C. Schmitter, Transitions from Authiritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 29-30 (membicarakan pengadilan selektif di Yunani. 53 Lihat H.L.A, Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford: Clarendon Press, 1968. 54 Untuk eksplorasi terhadap beberapa dari pertanyaan tersebut, lihat Sanford Levinson, “Responsibility for Crimes of War”, dalam Marshall Cohen et al. (eds.), War and Moral Responsibility, Princenton: Princenton University Press, 1974, 104; Richard Wasserstrom, “The Responsibility of the Individual for War Crimes”, dalam Virginia Held et al. (eds.), Philosophy, Morality, and International Affairs, New York: Oxford University Press, 1974, 47. Lihat juga Dennis F. Thompson, “Criminal Responsibility in Government”, dalam Roland Pennock dan John W. (eds.), Chapman Criminal Justice: Nomos XXVII, New York: New York University Press, 1985, 201-40. 18 akan mengancam kemampuan pengadilan suksesor untuk menaati kedaulatan hukum. Dalam hampir semua sistem hukum, baik Common Law, sipil maupun sosialis, tanggung jawab dibatasi oleh waktu dalam statuta pembatasan waktu. Jadi, mengadili kasus-kasus yang telah terjadi lama sebelumnya berarti tidak menaati aturan ini. Bagi kejahatan-kejahatan yang paling mengerikan – genosida atau penindasan menurut hukum internasional – norma-norma hukum internasional telah dimasukkan ke dalam hukum nasional, dengan tujuan untuk memediasi masalah penyelesaian dilema sifat keadilan transisional dalam sistem hukum domestik. Jadi misalnya di Hungaria, di mana terdapat batasan waktu 30 tahun yang mencegah pengadilan terhadap mereka yang bertanggung-jawab atas represi terhadap pemberontakan 1956, usaha untuk mencabut aturan tersebut dianggap inkonstitusional dan ex post facto. Namun, diberikan pengecualian terhadap kejahatankejahatan paling serius – kejahatan perang menurut hukum internasional – yang dianggap masih memiliki kekuatan normatif. Akomodasi serupa dilakukan di Polandia.55 Dilema perubahan norma ini tampak dalam pengadilan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kebijakan perbatasan di Jerman-bersatu. Tantangan berdasarkan legalitas umum, seperti asas retroaktivitas, dilawan oleh norma-norma alternatif yang ditarik dari hukum internasional (yang dijelaskan pada bab terdahulu tentang kedaulatan hukum). Pembatasan serupa mencegah pengadilan terhadap mantan menteri dalam negeri Rumania, dan kepala polisi rahasia, untu kejahatan yang dilakukan pada tahun 1954.56 Pada dekade 1990-an, mantan pejabat keamanan Polandia, termasuk Kepala Kementerian Keamanan Publik, diadili untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan antara tahun 1945 hingga 1952, berkaitan dengan penyiksaan dan pembunuhan tahanan politik; karena masalah waktu, pengadilan terhadap kejahatan era-Stalin ini membutuhkan pencabutan statuta pembatasan waktu oleh parlemen.57 Pada akhirnya akomodasi ini terbatas, seperti di Hungaria, pada kejahatan perang yang dapat diadili berdasarkan hukum internasional setelah jangka waktu yang panjang. Usaha serupa untuk melanggar hukum pembatasan waktu di Republik Ceko didukung Pengadilan Konstitusional.58 Dalam mengambil keputusan ini, pengadilan menyatakan bahwa pilihannya sukar, yaitu antara mendukung atau mengutuk legalitas rezim komunis yang lalu. Untuk menyelesaikan dilema ini, ketaatan terhadap statuta pembatasan waktu dan legalitas masa lalu dianggap sebagai masalah “prosedural”, sehingga memungkinkan pengadilan untuk terus berjalan atas nama transformasi politik. Mungkin kasus ekstrem dalam usaha untuk mengakomodasi respon pidana dalam konteks represi totaliter adalah pengadilan Jerman terhadap mantan kepala polisi rahasia Jerman Timur (Stasi), Erich Mielke. Ia dituntut pertanggungjawabannya terhadap tindakannya 55 Constitutional Court Decision on the Statute of Limitations, No. 2086/A/1991/14 (Hungaria, 1992), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe 1 (1994): 129, 136. Lihat Konstitusi Republik Polandia, Pasal 43. 56 Sebelum diadili untuk kasus pembunuhan, Alexandru Draghici melarikan diri ke Hungaria, yang menolak mengekstradisinya, dengan mengutip statuta pembatasan waktu 30 tahun. Lihat “Romanian Court Delays Trial of Ex-Securitate Boss”, Reuters, 28 Juni 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 57 Pada bulan November 1991, parlemen Polandia mencabut statuta pembatasan waktu bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan antara tahun 1946 dan 1952 untuk memungkinkan pengadilan pidana baru. Lihat “Former Security Officers Go to Trial for Torturing Prisoners”, UPI, 13 Oktober 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip UPI. 58 Law on the Illegality of the Communist Regime, Act No. 198/1993 (Republik Federal Ceko dan Slowakia, 1993). 19 di tahun 1931, ketika ia membunuh dua polisi pada hari-hari terakhir Republik Weimar – kejahatan berusia 61 tahun!59 Namun, menuntut Mielke atas pelanggaran yang dilakukan pada masa tersebut, lama sebelum ia menjadi tokoh komunis, hampir tidak memiliki kaitan dengan pelanggaran yang ia lakukan kemudian. Preseden transisional ini menunjukkan kesulitan mempertanggung jawabkan represi dalam pemahaman normal terhadap peradilan pidana. Melakukan pengadilan terhadap jajaran tertinggi kepemimpinan untuk kejahatankejahatan yang mengerikan, di pihak lain, terbatas pada kekerasan yang terjadi pada saat-saat terakhir kekuasaan komunis. Jadi, misalnya di Rumania, para asisten Nicolae Ceausescu diadili karena peran mereka dalam usaha merepresi pemberontakan anti-komunis pada tahun 1989.60 Di Republik Ceko, diajukan tuntutan kepada ketua partai komunis, mantan kepala pasukan keamanan Praha dan mantan menteri dalam negeri serta wakilnya atas represi brutal terhadap demonstrasi pada tahun 1988 dan 1989.61 Di Rusia, satu dari sedikit proses pengadilan yang dijalankan adalah pengadilan terhadap para pelaku kudeta militer (putsch) Agustus 1991.62 Namun, pengadilan-pengadilan ini tampaknya tidak menyentuh akar permasalahan. Pengadilan terhadap pelanggaran yang terjadi di saat-saat terakhir suatu rezim tampaknya bukanlah pesan normatif yang kuat untuk menentang pemerintahan totaliter. Pertanggungjawaban pidana telah berkembang pula atas dasar “pemerintahan yang buruk”, yang setelah runtuhnya komunisme berarti kejahatan ekonomi. Pada transisi dari ekonomi terpimpin ke sistem pasar bebas, pengadilan kejahatan ekonomi memiliki kekuatan transformatif yang penting. Seperti juga pengadilan-pengadilan pada transisi dari pemerintahan monarki di abad ke-18 menyerang institusi pemerintahan monarki, demikian juga pengadilan suksesor di abad ke-20 ini digunakan untuk mendelegitimasi komunisme. Pengadilan kejahatan ekonomi pasca-komunisme mengutuk nilai-nilai rezim terdahulu tentang kaitan normatif antara ekonomi dan negara. Pengadilan terhadap mantan pemimpin dilakukan untuk semua jenis kejahatan ekonomi: Pengadilan di Bulgaria adalah yang paling ambisius, dengan menuduh mantan pemimpin negeri itu, Todor Zhivkov, sebagai pencuri.63 Dalam pengadilan lainnya, mantan presiden Albania, Ramiz Alia, diadili untuk penyalahgunaan 59 Lihat, “Erich Mielke Sentenced to Six Years for 1931 Murders: Faces Other Charges,” This Week in Germany, 29 Oktober 1993, 2. 60 Lihat Adrian Dascalu, “Romania Jails Eight for 1989 Timisoara Uprising Massacre,” Reuters, 9 Desember 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 61 Miroslav Stepan, mantan ketua partai komunis Praha, diadili dan divonis pada tahun 1990. Lihat “Prague’s ExParty Boss Guilty of Abuse of Power”, Chicago Tribune, 10 Juli 1990, § 1, hlm. 4. Para menteri dalam negeri – Frantisek Kinel, Alojz Lorene dan Karel Vykypel – divonis pada bulan Oktober 1992. Lihat “Czechs Allow Prosecution of Communist Crimes”, Reuters, 10 Juli 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga “August 1998 – Gateway to Power for Number of Politicians”, CTK National News Wire, 18 Agustus 1998, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK. 62 Lihat Howard Witt, “Russians Whitewash Blame for 1991 Coup”, Chicago Tribune, 12 Agustus 1994, § 1, hlm. 1. Apa yang semula dikoar-koarkan sebagai “pengadilan abad ini” ketika dimulai pada bulan April 1993, berakhir dengan pembebasan salah satu tertuduh yang menolak menerima amnesti Februari 1994, dan menuntut namanya dibersihkan. 63 Lihat “Ousted Bulgarian Gets 7-Year Term for Embezzlement”, New York Times, 5 September 1992, hlm. A2. Lihat juga “Bulgarian Former Prime Minister Sentenced to Ten Years”, Reuters, 3 November 1992, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Namun, mahkamah agung negara tersebut membatalkan vonis tujuh tahun tersebut dan membebaskan Zhivkov pada tahun 1996. Lihat U.S. Department of State, Human Rights Country Reports (1997). 20 kekuasaan dan pencurian milik negara.64 Di Jerman, kepala federasi buruh Jerman Timur diadili karena mencuri uang milik serikat dan dituduh melakukan “penipuan terhadap hak milik sosialis”.65 Di Republik Ceko, mantan pemimpin komunis diajukan ke penyidikan pidana berkaitan dengan penghindaran pajak.66 Pelanggaran ekonomi dipusatkan pada pencurian “properti bersama”, meskipun properti demikian dan kejahatan serupa biasanya tidak ada lagi dalam masa pasca-komunis. Sebuah contoh lain adalah pengadilan di Moskow terhadap partai komunis.67 Meskipun terdapat preseden untuk memidana suatu organisasi, seperti di Nuremberg, keputusan tersebut biasanya dijadikan dasar untuk melakukan pengadilan individual.68 Pengadilan individual didasarkan pada keanggotaan organisasi pidana. “Buah pikiran Bernay”, demikian sebuah konsep dinamakan menurut pengacara yang merancang prosedur tersebut, dikembangkan untuk mengatasi halangan praktis dan pembuktian untuk pengadilan terhadap ribuan anggota SS atas kekejaman yang mereka lakukan. Dalam penggunaan prosedur pidana yang tidak konvensional, pengadilan Moskow menguji batasan-batasan hukum pidana untuk keadilan transisional. Sejauh praktik partai dapat ditunjukkan melanggar hukum dan korup, usahanya adalah untuk menjadikan komunisme berada di luar lingkup pilihan politik yang sah. Pengadilan serupa terhadap rezim pendahulu dilakukan di Ethiopia dalam transisi pascaMarxisnya.69 Bila pengadilan diadakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan sistem ekonomi lama yang sudah kehilangan pengaruh dengan perubahan rezim ekonomi, hal ini menggambarkan pula masalah retroaktivitas yang mempengaruhi keadilan suksesor, karena tidak memiliki prospektivitas legal. Pengadilan suksesor sering kali menimbulkan masalah ex post facto dengan mengadili tindakan-tindakan lama yang baru dianggap sebagai pelanggaran, dan tidak menaati prinsip prospektivitas atau melindungi legalitas konvensional serupa. Meskipun rezim transisional sering kali berusaha untuk menuntut pertanggungjawaban mantan pemimpinnya, dilemanya adalah sering kali pelanggaran terberat yang dilakukan dalam masa itu tidak bisa dibebankan pada para pemimpin. Bahkan, sering kali sukar untuk menemukan kaitan antara pimpinan politik dan pelanggaran-pelanggaran terburuk dalam pemerintahan represif, sehingga dalam pengadilan suksesor, pemimpin hanya diadili untuk pelanggaran lain yang tidak penting. Bila kebijakan peradilan pidana diarahkan untuk mengadili kesalahan “kecil” para mantan pemimpin, pengadilan suksesor paling rentan terhadap persepsi tentang keadilan yang terpolitisasi. Pengadilan demikian akan bertentangan dengan intuisi kita tentang ketaatan terhadap kedaulatan hukum. 64 Lihat “Last Communist President Jailed for Five Years”, Agence France-Presse, 2 Juli 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Curnws. 65 Lihat “Former German Labor Boss Convicted of Fraud, Released”, Washington Post, 7 Juni 1991, hlm. A18. 66 Lihat misalnya, “Czech Republic: Slovakia Asked about Communist’s Tax Exemption”, Reuters, 30 Januari 1995, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 67 Yuri Feofanov, “The Estabilishment of the Constitutional Court in Rusia and the Communist Party Case”, Review of Central and East European Law 19, No. 6 (1993): 623-37. Untuk transkrip dalam bahasa Inggris tentang konferensi pers di mana para penuntut menjelaskan tujuan dan strategi hukum pengadilan, lihat Official Kremlin International News Broadcast, 6 Juli 1992, tersedia di Lexis, News Library. Untuk laporan jurnalistik, lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30 November 1992, hlm. 104. 68 Lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 35-36. Namun, pada akhirnya ada pergeseran ke proses administratif. Lihat bab 5. 69 Proclamation Establishing the Office of Special Prosecutor, pembukaan, No. 22/1992 (Ethiopia, 1992). 21 Dalam pengadilan suksesor lainnya yang diadakan di tingkat nasional, proses pengadilan tidak selalu diarahkan pada jajaran tertinggi, namun terhadap mereka yang bertanggung-jawab karena melakukan pelanggaran terburuk. Kebijakan penghukuman ini bisa menyentuh jajaran terbawah dalam negara represif, hingga para polisi dan anggota militer yang secara langsung melakukan kekejaman. Sebuah contoh penting adalah “pengadilan penyiksa” di Yunani pada tahun 1975.70 Sebuah contoh lebih mutakhir adalah pengadilan terhadap para penjaga perbatasan di Jerman. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa terdapat kesulitan untuk menjalankan peradilan suksesor dari perspektif kerangka kejahatan yang biasa. Meskipun kebijakan penghukuman demikian dapat mengidentifikasi dan mengutuk pelanggaran yang dilakukan rezim pendahulu, namun kasus-kasus tersebut menimbulkan dilema kedaulatan hukum yang signifikan. Di satu sisi kasus-kasus tersebut menerapkan nilai keberlakuan hukum secara umum dan setara, namun di sisi lain kasus-kasus itu juga mencoba mencari celah dari aturan ini. Kesetaraan di muka hukum bersifat mutlak; dalam pengadilan terhadap mereka yang terkait dengan pelanggaran di masa lalu, terdapat suatu selektivitas dalam kebijakan pengadilan, yang merupakan dilema sentral dalam penggunaan hukum pidana untuk membangun transisi demokratik. Masalah Tanggung Jawab dalam Transisi Pengadilan suksesor yang dibicarakan di atas menunjukkan bahwa sukar untuk mengkonseptualkan dan menerapkan pemahaman biasa tentang tindakan pidana dalam hukum domestik setelah berakhirnya rezim represif. Karena, peradilan pidana suksesor memunculkan permasalahan tentang siapa yang menjadi subjek kebijakan penghukuman. Apa standar pertanggungjawaban yang tepat digunakan dalam pergantian rezim, dari sentralisasi ke kebebasan individual? Apakah sebaiknya sistem penetapan hukuman mengikuti model pemahaman tanggung jawab yang ada dalam rezim totaliter dan otoriter? Atau hukum harus menjadi transformatif dan mengikuti pemahaman tanggung jawab seperti di negara liberal? Dan sejauh mana hukum pidana memiliki peran dalam pergeseran politik? Pada akhir abad ke-20, ada indikasi bahwa terdapat ekspansi potensi pertanggungjawaban pidana: Setelah Nuremberg, baik pemimpin maupun serdadu sama-sama memiliki tanggung jawab untuk pelanggaran negara. Bagaimana mengkonseptualisasi tanggung jawab dalam hierarki kekuasaan? Sejauh mana seharusnya pemimpin dan bawahan dituntut pertanggungjawaban mereka untuk tindak pidana yang sama? Apakah pembebanan tanggung jawab pidana kepada salah satu berarti bahwa pihak yang lain memiliki tanggung jawab yang lebih kecil; apakah mengadili atasan berarti membebaskan bawahan, dan sebaliknya? Sebagai masalah praktis, pada tingkat pembuktian, terdapat kaitan yang tak dapat dibantah dalam pertanggungjawaban hukum para pemimpin dan bawahan mereka. Tanggung jawab komando dapat dibuktikan dari atas, bergantung pada bukti adanya kebijakan yang melanggar hukum di tingkat atas, atau sebaliknya, bila bawahan merujuk pada pembelaan 70 Di kalangan para analis hak asasi manusia, pengadilan “para penyiksa” Yunani dianggap sebagai model ideal pengadilan suksesor. Lihat Orentlicher, “Settling Accounts”, 2598. Untuk tinjauan mendetail tentang Pengadilan militer Yunani, Lihat Amnesty International, Torture in Greece: The First Torturer’s Trial, 1975, London: Amnesty International, 1877. Untuk pembicaraan tentang pengadilan selektif Yunani, lihat O’Donnell dan Schmitter, Transitions: Tentative Conclusions, 29-30. 22 ketaatan pada perintah atasan, dibuktikan dari bawah, dari bukti adanya kejahatan di tingkat bawah. Aspek problematik dalam keadilan transisional tergambar baik di pengadilan suksesor pasca-perang maupun kontemporer, seperti pengadilan para anggota militer Argentina dan pengadilan Jerman-bersatu yang terkait penembakan di Tembok Berlin. Secara historis, pertanyaan tentang relativitas tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah yang represif timbul dari pengadilan nasional Jerman untuk kekejaman yang terkait Perang Dunia Kedua. Kasus-kasus demikian memunculkan masalah bagaimana membebankan tanggung jawab pidana dalam suatu spektrum politik. Sebagai contoh, dalam kasus pembantaian brutal empat ribu orang di dekat perbatasan Lithuania, pengadilan daerah Ulm mengalami kesulitan dalam menentukan tanggung jawab tersangka. Adolf Hitler dan lingkaran terdekatnya dianggap sebagai “pelaku utama” tindakan pemusnahan tersebut, sementara para tersangka dalam kasus itu dianggap sebagai “rekan dalam kejahatan” – yang memberikan kontribusi terhadap tindakan para pelaku utama. Dalam kasus-kasus ini, pengadilan nasional tampaknya memiliki pendekatan zero sum terhadap tanggung jawab pidana, yang pada akhirnya membatasi pertanggungjawaban total terhadap kesalahan di masa lalu.71 Masalah relativitas tanggung jawab dalam transisi ini tampak jelas dalam pengadilan Jerman-bersatu terhadap penembakan hingga tewas di Tembok Berlin. Selama hampir setengah abad, Tembok Berlin adalah simbol internasional utama represi komunis. Tempat tersebut menyaksikan usaha-usaha untuk melarikan diri ke kebebasan dan penembakan atas perintah negara, menggambarkan totalitas kekangan komunis, dan keruntuhannya melambangkan perubahan politik masif di wilayah tersebut. Setelah runtuhnya tembok tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana membebankan tanggung jawab pidana ketika represi dirancang oleh para pemimpin politik namun dilaksanakan oleh para penjaga. Pengadilan terhadap kasus penembakan Tembok Berlin terlihat tidak berimbang, karena banyak penjaga berpangkat rendah diadili sementara tidak ada tuntutan untuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak atasan. Dalam kasus utama, dua penjaga dijatuhi hukuman karena melakukan penembakan hingga tewas di perbatasan, meskipun mereka mengaku hanya mengikuti perintah.72 Penghukuman tersebut sebenarnya merupakan afirmasi terhadap prinsip Nuremberg, yaitu bahwa pembelaan ketaatan pada perintah harus dikalahkan oleh tanggung jawab individual; namun, hal ini tidak didukung dengan penerapan prinsip serupa terhadap para atasan. Meskipun mantan pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker dan lima pejabat senior lainnya dituduh mengotaki kebijakan “tembak mati” di perbatasan, hampir semua tuduhan dicabut.73 Sedikit tuduhan yang menghasilkan keputusan memberikan 71 Rückerl, Investigation of Nazi Crimes, 48, 137. Lihat Judgment of Jan. 20, 1992, Juristenzeitung 13 (1992): 691, 692 (F.R.G. Landgericht [LG] [Berlin]), Stephen Kinzer, “2 East German Guards Convicted of Killing Man as He Fled to West”, New York Times, 21 Januari 1992, rubrik internasional. 73 Meskipun mantan pemimpin komunis, Egon Krenz dan ideolog partai Kirt Hager juga menjadi tertuduh, sukar untuk mendapatkan bukti yang mengaitkan mereka dengan penembakan. Willi Stoph, mantan perdana menteri, dan Erich Mielke, mantan kepala polisi rahasia, dibebaskan dari pengadilan karena alasan kesehatan. Lihat Stephen Kinzer, “Germany Frees Ailing Honecker, Who Flies to Chile”, New York Times, 14 Januari 1993, rubrik internasional. Tuntutan terhadap Honecker kemudian dibatalkan. Streletz, Albrecht dan Kessler, didakwa pada tanggal 16 September 1993, tetapi kemudian dibebaskan dari penjara karena alasan kesehatan. Lihat Rick Atkinson, “3 Ex-East German Officials Sentenced: Former Top Communists Found Guilty in Deaths of Refugees”, Washington Post, 17 September 1993; Leon Mangasarian, “East German Leaders Found Guilty of 72 23 hukuman minimal. Bila para arsitek utama kebijakan “tembak mati” suatu negara bebas dari tanggung jawab, prinsip tanggung jawab individual menjadi tampak lemah. Pertimbangkanlah mengapa demikian. Kasus penjaga perbatasan ini seharusnya menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat antara tanggung jawab komandan dan bawahan untuk kejahatan yang dilakukan dalam pemerintahan yang represif secara sistematis. Dilema tanggung jawab individual ini harusnya diselesaikan dengan membebankan tanggung jawab yang sama kepada dalang maupun pelaku. Dilema pasca-totaliter yang dijelaskan di atas juga tampak dalam transisi lainnya. Setelah pemerintahan militer, bagaimana mengkonseptualisasi tanggung jawab hukum para komandan dan bawahan untuk kekejaman dalam negara polisi? Bila satu orang memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan, siapa “pelaku” kejahatan tersebut? Inilah pertanyaan utama dalam pengadilan suksesor di Argentina terhadap junta militernya. Teori “tanggung jawab bersama” yang diajukan oleh pengadilan tingkat rendah menganggap bahwa tanggung jawab atasan sama tingginya dengan tanggung jawab bawahan untuk pelanggaran yang sama, menurut doktrin “kendali tindakan” yang berasal dari Jerman, yang membebankan tanggung jawab pidana kepada pelaku langsung maupun tidak langsung. Maka, junta tersebut dianggap bertanggung-jawab atas perannya sebagai perencana dan pemberi perintah penyiksaan dan penghilangan, sebagai “pelaku tidak langsung”, sementara orangorang lain yang terlibat dianggap sebagai “pelaku langsung”.74 Namun, setelah banding, “tanggung jawab bersama” ini dimodifikasi oleh Mahkamah Agung yang berusaha untuk menerapkan pemahaman normal tentang tanggung jawab pidana terhadap kejahatan aparat represi. “Keberadaan pada saat yang sama dua tingkat tanggung jawab kejahatan tidak memiliki dasar,” menurut Mahkamah Agung, karena jika seseorang bertanggung-jawab terhadap terjadinya suatu kejahatan, ia memiliki “kendali tindakan”, sehingga tidak ada tanggung jawab sebagai pelaku “tidak langsung” pada posisi komandan. Dengan demikian, para komandan dianggap sebagai “rekan dalam kejahatan” penindasan.75 Karakterisasi tanggung jawab pidana ini tampak aneh, karena para pelaku utama represi negara malah dianggap sebagai agen. Preseden junta mengabaikan signifikansi peran Wall Killings but Set Free, UPI, 16 September 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip UPI. Egon Krenz diadili bersama lima anggota politbiro lainnya atas tuduhan pembunuhan dalam peristiwa Tembok Berlin. Krenz dijatuhi vonis pada bulan Agustus 1997 untuk enam setengah tahun penjara. Dua pejabat tinggi politbiro lainnya masing masing dihukum tiga tahun. Lihat “Senior East German Officers Jailed for Berlin Wall Killings”, Deutscher Presse Agentur, 26 Maret 1998, tersedia di Lexis, News Library. “Hingga tahun 1997, terdapat 50 kasus yang dibawa ke pengadilan terhadap sekitar 100 serdadu, perwira dan pejabat pemerintah yang dituduh berkaitan penembakan di Tembok Berlin. Dari jumlah itu, 55 telah mendapatkan vonis. Hampir semua mendapatkan hukuman yang singkat atau ditunda. Edmund Andrews, “Honecker’s Succesor Jailed for Wall Killings”, International Herald Tribune, 26 Agustus 1997, tersedia di Lexis, News Library. Untuk diskusi doktrinal tentang kasus-kasus ini, lihat German Yearbook of International Law 36 (Berlin, 1993): 41. Untuk laporan jurnalistik, lihat Rosenberg, Haunted Land. 74 Proses peradilan terhadap Jorge R. Videla et al. semula diajukan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mengikuti Dekrit No. 158. Judgment of December 9, 1986 bagian 308-314 (Federal Criminal and Correctional Court of Appeals, Federal District of Buenos Aires), sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Alejandro M. Garro dan Henry Dahl, “Legal Accountability of Human Rights Violations in Argentina: One Step Forward and Two Steps Backward”, Human Rights Law Journal 8 (1978): 417-18. Lihat Paula K. Speck, The Trial of Argentine Junta: Responsibilities and Realities,” Inter-American Law Review 18 (1987): 491. 75 Judgment of December 30, 1986 bagian 23-29, 48-49 (Mahkamah Agung Argentina, Buenos Aires). Sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Garro dan Dahl, “Legal Accountability for Human Rights Violations in Argentina,” 435-39. 24 pejabat tinggi dalam penindasan. Terlebih lagi, dampak dari pandangan ini amat kuat. Meskipun para komandan tersebut hanya diancam untuk hukuman yang ringan, pengadilan mereka sebagai “aktor tidak langsung” tampaknya memungkinkan pembatasan tanggung jawab pada tingkat bawah, yang pada akhirnya dapat melemahkan kebijakan pengadilan tersebut. Pengakuan terhadap tanggung jawab para komandan sebagai pelaku kebijakan penindasan mendorong pembelaan “ketaatan pada perintah” oleh para bawahan, dan menghindarkan diri dari tanggung jawab individual. Setelah perlawanan keras dari milter terhadap proses pengadilan tersebut, pembelaan ketaatan pada perintah ini dihidupkan kembali sebagai cara untuk membatasi jumlah potensial kasus yang dibawa ke pengadilan, dan hanya memungkinkan tindakan “amat kejam” yang melangkahi perintah yang diberikan. Pada akhirnya, proses pengadilan terhadap kasus-kasus demikian pun dihentikan. Kegagalan program pengadilan suksesor di Argentina menggambarkan konsekuensi berisiko dari usaha untuk memberikan hukuman dalam konteks ekspansi pemahaman tanggung jawab kontemporer, namun dalam kondisi transisional. Tanpa prinsip pembatasan yang jelas, sebagian besar anggota angkatan bersenjata negara tersebut terancam untuk diajukan ke pengadilan, suatu bayangan yang menimbulkan instabilitas, sehingga pada akhirnya, menghasilkan pemgampunan dan amnesti sistemik.76 Kebijakan pengadilan Argentina setelah masa pemerintahan militer sebenarnya rentan karena bermula pada junta militer yang memerintah, namun terhenti pada jajaran bawah. Demikian pula, kebijakan pengadilan Jerman setelah komunisme juga rentan karena gagal mengadili mereka yang berada di jajaran atas. Kedua pengalaman pengadilan suksesor ini menunjukan kesukaran untuk membangun pesan normatif perubahan menuju liberalisasi. Penuntutan tanggung jawab individual untuk kejahatan yang dilakukan dalam kerangka represi sistemik menimbulkan dilema pertanggungjawaban. Pertanyaannya adalah kepada siapa dibebankan pertanggungjawaban setelah represi yang sistemik. Praktik suksesor yang dibicarakan di sini menunjukan bahwa kejahatan sistemik tidak bisa dijawab dengan pemahaman normal tentang tanggung jawab pidana dan prinsip pemandu yang relevan. Tindakan kesalahan secara sistemik terjadi dalam spektrum kekuasaan dari pemimpin hingga bawahan, menyulitkan pemberian sanksi pidana. Pada akhirnya, tingkat pertanggungjawaban yang tepat harus didapatkan dari kebijakan yang memiliki andil terhadap pelanggaran, yang mencirikan represi kontemporer. Sanksi Pidana Terbatas Praktik transisional selama setengah abad terakhir menunjukan bahwa selalu terdapat masalah peradilan yang ditimbulkan dari pergeseran norma paradigmatik yang mencirikan transisi. Kompromi terhadap keadilan ini memberikan batasan sekaligus memungkinkan pelaksanaan kekuasaan penghukuman dalam transisi. Meskipun terdapat ekspansi dramatik dalam pertanggungjawaban pidana pada tingkat abstrak, pelaksanaannya masih tertinggal jauh. Praktik suksesor menunjukan suatu pola penyelidikan pidana yang dilanjutkan proses pengadilan, namun dengan sanksi yang ringan atau tidak ada sama sekali. Sementara hukuman 76 Untuk tinjauan tentang bagaimana militer menyatukan kekuatan untuk melawan ancaman hukuman, lihat Jaime Malamud-Goti, “Trying Violators of Human Rights: The Dilemma of Transitional Democratic Governments”, dalam State Crimes: Punishment of Pardon, Queenstown, Md: Aspen Institute, 1989, 71-88. 25 secara umum dikonseptualkan sebagai praktik tunggal yang mencakup proses penentuan dan penghukuman kesalahan, dalam sanksi pidana transisional, elemen-elemen penentuan dan pemberian sanksi menjadi terpisah satu sama lain. Proses pidana parsial yang menyusul, yang dikenal sebagai sanksi “terbatas” adalah yang membedakan peradilan pidana dalam transisi. “Sanksi pidana terbatas” mencakup proses pengadilan yang belum tentu berpuncak pada pemberian hukuman maksimum. Dalam sanksi terbatas, tahap-tahap penentuan kesalahan dan pemberian sanksi dipisahkan. Bergantung pada batasan proses pemberian sanksi, penyidikan bisa berakhir pada tuduhan, ajudikasi atau vonis. Terlebih lagi, vonis yang diberikan biasanya ringan atau tanpa hukuman. Jadi, dalam masa transisi, sanksi pidana sering kali dibatasi pada penyelidikan untuk membuktikan kesalahan. Pemberian keputusan tentang adanya tindakan salah, bukan terhadap tertuduh ini merupakan ciri dari beberapa negara yang menganut hukum sipil.77 Jadi, di Jerman, badan pengadilan memiliki tugas independen berupa Aufklärungspflicht, “penyelidikan atau klarifikasi”, tentang adanya tindakan salah, yang terpisah dari kebersalahan tertuduh.78 Namun, sanksi pidana terbatas melangkah lebih jauh dalam peradilan transisional yang khas pada kondisi transisional. Pembatasan sanksi pidana dalam transisi tergambarkan dalam sejarah: pada pengadilan pasca-perang Dunia Pertama,79 dalam kasus-kasus Perang Dunia Kedua, dan pengadilan pasca-kekuasaan militer di Eropa Selatan, dan juga peradilan pidana suksesor kontemporer di Amerika Latin dan Afrika, dan yang paling mutakhir, gelombang perubahan politik di Eropa Tengah setelah keruntuhan Soviet. Peradilan suksesor pasca-Perang Dunia Kedua merupakan contoh baik pemberian sanksi pidana terbatas, meskipun ini adalah sisi yang kurang terkenal dari pemahaman keadilan pasca-perang ini. Setelah diadakan Tribunal Militer Internasional dan ketika pengadilan Allied Control Council No. 10 masih berjalan, terdapat perubahan kebijakan penghukuman. Antara tahun 1946 hingga 1958, suatu proses peninjauan dan pengampunan berakhir dengan pengurangan sanksi secara besar-besaran bagi para penjahat perang Jerman. Banyak orang yang dijatuhi hukuman dalam pengadilan Control Council No. 10 oleh otoritas pendudukan praktis tidak dihukum, melalui program pengampunan yang diawasi Komisioner Tinggi Amerika Serikat, John McCloy.80 Urutan serupa dapat diamati pada pengadilan nasional Jerman. Dari lebih dari 1000 kasus yang diadili antara tahun 1955 dan 1969, kurang dari 100 terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup, dan kurang dari 300 mendapat hukuman yang lebih ringan.81 Bertahun-tahun kemudian, urutan serupa terjadi pula dalam transisi Eropa Selatan. Pengadilan terhadap polisi militer di Yunani berakhir dengan hukuman yang singkat atau dapat dikurangi. Posisi pemerintah adalah bahwa pengadilan dan pendakwaan sudah memenuhi keadilan, dan sebaliknya, “pada tahap akhir, tanggung jawab politis yang tinggi 77 Lihat John Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, 1985. Lihat § 155 (II) StPO (pengadilan diwajibkan bertindak secara independen). Lihat German Code of Criminal Procedure, Vol. 10 (C), “Principles of Proof”, John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure: Germany, St. Paul: West Publishing, 1977. 79 Lihat Sheldon Glueck, War Criminals: Their Prosecution and Punishment, New York: Knopf, 1944, 19-36, untuk tinjauan sejarah tentang tindakan yang diambil terhadap penjahat perang Jerman menurut Perjanjian Versailles. Lihat juga James P. Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing War Criminals of the First World War, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982, 116-39, 174-76 (membicarakan usaha penghukuman pasca-Perang Dunia Pertama). 80 Lihat Frank M. Buscher, The U.S. War Crimes Trial Program in Germany, 1946-1955, New York: Greenwood Publishing Group, 1989, 62-64. 81 Lihat umumnya Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy. 78 26 harus diutamakan”.82 Pola serupa tampak dalam transisi dari pemerintahan militer di Amerika Latin. Segera setelah dekade 1980-an, pengadilan junta militer Argentina mulai melakukan batasan terhadap pengadilan lebih lanjut, dan memberikan pengampunan.83 Sementara pada awal transisi militer diancam oleh hukuman, secara progresif ancaman tersebut dikikis – pertama melalui pengampunan oleh presiden, dan kemudian melalui keputusan legislatif yang membatasi jurisdiksi dan memberikan amnesti umum (blanket amnesty). Pada akhirnya, pengampunan presiden diberikan secara luas kepada semua orang yang dituduh melakukan kekejaman, termasuk para pemimpin tertinggi junta militer. Amnesti diterima sebagai hal yang umum di seluruh wilayah benua tersebut, misalnya di Cili, Nikaragua dan El Salvador, yang dampaknya akan dibicarakan lebih lanjut dalam bab ini. Kisah ini terulang lagi dalam pengadilan suksesor setelah keruntuhan komunis. Sepuluh tahun setelah revolusi, dan di seluruh wilayah Eropa, terlihat penerapan sanksi yang terbatas. Dalam pengadilan penjaga perbatasan Jerman, penangguhan penjatuhan hukuman menjadi norma,84 demikian pula di Republik Ceko. Di Romania, para mantan pemimpin komunis dan polisi yang dipenjara berkaitan dengan pembantaian pada bulan Desember 1989 dibebaskan dalam jangka waktu dua tahun, baik karena alasan kesehatan atau karena pengampunan dari presiden. Di Bulgaria, usaha terpenting untuk melakukan penghukuman gagal; Todor Zhivkov tidak menjalani hukumannya untuk kasus pencurian, sementara orangorang lainnya mendapatkan pengampunan. Di Albania, sebuah hukum amnesti memberikan kekebalan bagi banyak mantan pemimpin rezim lama yang dihukum untuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk presiden komunis terakhir negara itu. Selama sekitar lima tahun transisi di wilayah tersebut, arah perkembangan menunjukkan lemahnya penerapan tahap terakhir kebijakan penghukuman ini. Sebagaimana terlihat dari sejarah, terdapat batasan de facto terhadap sanksi pidana. Fenomena yang sama terlihat di wilayah-wilayah lainnya. Di Korea Selatan pascakediktatoran, para presiden yang didakwa melakukan korupsi akhirnya diampuni setelah 82 Amnesty Internasional, Torture in Greece, 65. Diamandouros, “Regime Change and the Prospects for Democracy in Greece: 1974-1983”, 138-64, 161. 83 Lihat “Argentine Seeks Rights-Trial Curb: Alfonsin Urges a Time Limit on Prosecution for Abuses under Military Rule”, New York Times, 6 Desember 1986, rubrik internasional. Lihat juga “200 Military Officers Are Pardoned in Argentina”, New York Times, 8 Oktober 1989, rubrik internasional, hlm. 12. Tentang gelombang kedua pemberian pengampunan, lihat Shirley Cristian, “In Echo of the ‘Dirty War’ Argentines Fight Pardons”, New York Times, 28 Desember 1990, rubrik internasional, hlm. A3. Lihat juga Americas Watch, Truth and Justice in Argentina: An Update, New York: Human Rights Watch, 1991; Carlos Nino, “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina”, Yale Law Journal 100 (1991): 1619. Perkembangan terakhir di Argentina bertentangan dengan gejala ini. Lihat “President Says He Won’t Veto Repeal of Amnesty Laws”, Agence France-Presse, Buenos Aires, 26 Maret 1998; Marcela Valente, “Rights-Argentina: Dissatisfaction with Repeal of Amnesty Laws”, Inter Press Service, Buenos Aires, 25 Maret 1998. 84 Untuk tinjauan tentang kasus penjaga perbatasan, lihat Micah Goodman, “After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany”, Cornell International Law Journal 29 (1996): 727. Lihat juga “Former Albanian President Has Sentence Cut by Three Years”, Agence France Presse, 30 November 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip AFP; Henry Kamm, “President of Albania Rebuffed on Charter”, New York Times, 1 Desember 1994, tersedia di Lexis, News Library; “28 Communist Officials Tried for Antoconstitutional Activity”, CTK National News Wire, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK (vonis terhadap mantan menteri keuangan Cekoslowakia Zak dan Ler); “Romanians Protest over Communist Bosses Release”, Reuters World Service, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 27 sebentar menjalani hukuman. Di Cili, meskipun terdapat hukum yang mengecualikan militer dari pengadilan, pengecualian ini bersyarat pada kerja sama para perwira tersebut dalam penyelidikan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pada masa pemerintahan militer.85 Ancaman sanksi langsung dihilangkan asal mereka bersedia mengaku melakukan kesalahan. Hal yang sama juga terjadi di Afrika Selatan pasca-apartheid: pemberian amnesti terhadap kejahatan politik masih memberikan kesempatan untuk penyelidikan terhadap pelanggaran di masa lalu dan melakukan proses pengadilan yang terbatas.86 Respon hukum kontemporer lainnya, seperti tribunal internasional ad hoc yang dibentuk untuk mengadili genosida dan kejahatan perang, mencerminkan perkembangan yang serupa. Tribunal pidana internasional yang dibentuk untuk mengadili kekejaman yang terjadi di bekas Yugoslavia dan Rwanda menunjukkan pemahaman terhadap sanksi terbatas ini.87 Usaha untuk mencapai keadilan dalam perdamaian yang rapuh memiliki konsekuensi signifikan untuk penerapan hukum pidana secara efektif, yaitu kemungkinan untuk melakukan pengadilan dan memberikan sanksi, sehingga membatasi sanksi pidana dalam kondisi demikian. Misalnya, ketiadaan proses penahanan terhadap tertuduh, dan ketiadaan kendali terhadap bukti dan adanya batasan yang terkait dengan pengadilan kejahatan perang, menyebabkan tribunal internasional sering kali tidak memiliki pilihan selain melakukan penyelidikan dan mengajukan tuduhan – dan hanya sampai di situ. Jadi proses internasional tersebut menimbulkan suatu model baru: suatu prosedur gabungan antara tuduhan dan dakwaan yang mencerminan sanksi terbatas. Dalam prosiding superindictment (dakwaan paling berat) yang disediakan dalam aturan-aturan tribunal, semua bukti yang tersedia dikumpulkan dan dibacakan secara publik,88 dan dakwaan tersebut dikonfirmasi, meskipun si tertuduh tidak hadir, dan dengan demikian secara terbuka menentukan kebenaran tentang peristiwa yang dipermasalahkan dan mengutuknya. Proses ini memungkinkan penentuan kesalahan di balik pelanggaran tersebut, dan juga mengesahkan keputusan yang formal dan publik. Peradilan Pidana Terbatas dan Konstruksi Transisi Pertimbangkanlah signifikansi sanksi pidana terbatas bagi transisi politik. Mengapa, meskipun dengan hasil terbatas dari pengadilan suksesor yang dibahas di muka, tetap ada persepsi umum 85 Lihat Human Rights Watch Americas, Unsettled Business: Human Rights in Chile at the Start of the FREI Presidency, New York: Human Rights Watch, 1994, 1-4. 86 Lihat Azanian Peoples Organisation (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa and Others, 1996 (8) BCLR 1015 (CC) (menjunjung konstitusionalitas undang-undang amnesti); Lourens du Plessis, “Amnesty and Transition in South Africa”, dalam Alex Boraine et al. (eds.), Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, Cape Town: Institute for Democracy in South Africa, 1994. 87 Tribunal tersebut dibentuk untuk tujuan “pengadilan terhadap orang-orang yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Lihat Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the U.N. Security Council Resolution 808, S/25704 (1993). 88 Lihat International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia Since 1991: Rules for Procedure and Evidence, aturan 61, dicetak ulang dalam International Legal Materials 33 (1994): 519. Istilah superindictment digunakan untuk kepentingan internal tribunal. Lihat Graham Blewitt, wakil penuntut untuk Tribunal Yugoslavia, wawancara dengan penulis, Waldorf Astoria Hotel, New York, 7 April 1995. 28 bahwa di Tribunal Nuremberg, Pengadilan Militer Yunani, dan Pengadilan Federal Buenos Aires, keadilan telah tercapai? Meskipun tidak diberi hukuman maksimum, sanksi pidana transisional tampaknya menjadi simbol kedaulatan hukum. Intuisi kita tentang pemberian hukuman adalah dengan menjustifikasikannya dalam keterkaitannya dengan pelanggaran spesifik dan hukuman terhadap pelaku individual, sementara sanksi pidana terbatas dijustifikasi secara umum untuk tujuan-tujuan yang melampaui kejahatan spesifik, dalam kondisi transisional. Sementara intuisi kita adalah bahwa sifat dan peran sanksi pidana itu kaku, dan stabilitas dianggap sebagai norma inti kedaulatan hukum, sanksi transisional menunjukkan peran dinamik peradilan pidana dalam memajukan perubahan normatif. Praktik pemberian hukuman dalam masa-masa ini memajukan kepentingan transformasi dalam kondisi transisi. Dalam sanksi pidana terbatas, hukum memediasi transisi. Tujuannya adalah untuk melihat ke belakang dan ke depan, retrospektif dan prospektif, diskontinu dan kontinu. Pemisahan dari rezim pendahulu diajukan dengan praktik-praktik pemberian hukuman; mengadili kesalahan pendahulu berarti meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan bila masalah pertanggungjawaban untuk kejahatan masa lalu tidak sepenuhnya diselesaikan, penentuan kejahatan-kejahatan di masa lalu dapat memajukan tujuan-tujuan penting yang berkait dengan pemberian hukuman, seperti klarifikasi kejahatan lama yang menimbulkan kontroversi.89 Sanksi terbatas memungkinkan penyelidikan dan pengutukan terhadap kejahatan masa lalu. Proses pidana dipergunakan untuk menyelidiki, menentukan dan mengutuk kesalahan dengan signifikansi lebih luas daripada sekadar kontroversi khusus antara para pelaku suatu pelanggaran tertentu dan korbannya, ke seluruh masyarakat luas yang mengalami pergolakan politik. Fungsi klarifikasi dari penyelidikan pidana transisional, yaitu tujuan “epistemik”-nya, berasal dari arti “penuntutan” (prosecution) dari abad ke-16, yaitu untuk mengetahui fakta secara jelas, untuk memperoleh detail-detail dari suatu permasalahan.90 Penyelidikan pidana formal memungkinkan penemuan fakta tentang suatu kejahatan yang kontroversial, dilakukan dalam proses pidana dengan standar pengetahuan yang tinggi dan melalui prosedur publik yang formal. Pada masa gejolak politik, pelanggaran yang dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya memiliki dimensi publik yaitu kebijakan negara, sehingga penyelidikan pidana memungkinkan sebuah negara untuk membangun masa lalu negara yang disepakati bersama melalui ritual publik kolektif. Dan, meskipun pengetahuan yang didapatkan dari catatan pengadilan atau penyelidikan pidana tampaknya lebih terbatas daripada pencatatan sejarah yang lebih mendetail, ia masih tetap berguna dalam masa transisi. Peradilan pidana transisional memungkinkan suatu bentuk penyelidikan yang sangat terkendali dan terbatas terhadap masa lalu. Melalui proses pengajuan tuntutan, rezim suksesor di suatu negara secara efektif mengendalikan arah penyelidikan sejarah, menjelaskan masa lalu politik yang gelap dari suatu negara. Bahkan dalam bentuknya yang terbatas, sanksi pidana transisional memajukan kepentingan untuk menentukan dan mengutuk pelanggaran di masa lalu. Sanksi transisional yang terbatas ini menawarkan resolusi pragmatis terhadap dilema utama transisi, yaitu masalah pertanggungjawaban individual untuk pelanggaran sistemik yang dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu yang represif. Timbulnya sanksi terbatas ini 89 Lihat Joel Feinberg, Doing and Deserving – Essays in the Theory of Responsibility, Priceton: Princeton University Press, 1970. Lihat juga Joel Feinberg, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, New York: Oxford University Press, 1084. 90 Lihat Oxford English Dictionary, edisi kedua, pada entri “prosecution”. 29 menunjukkan cara pikir yang lebih fleksibel tentang apa kegunaan penghukuman, dengan menunjukkan kesalahan tanpa harus membebankan kesalahan atau hukuman. Sementara dalam teori penghukuman (penal theory) yang umum, justifikasi retributif yang berkaitan dengan hukuman dianggap sebagai praktik yang menyatu-padu, sanksi dalam transisi mendorong pemikiran kembali tentang teori penghukuman dan justifikasinya dengan mengaitkannya lebih dekat dengan berbagai tahapan dalam proses pidana. Sanksi transisional menunjukkan cara alternatif untuk pemikiran ide retributif.91 Meskipun sanksi transisional dicirikan oleh keterbatasan hukuman, pengalaman di atas menunjukkan bahwa tujuan utama, yaitu penjatuhan hukuman, dapat dicapai dengan pemberian hukuman yang ringan – bahkan simbolis. Tujuan retributif utama yang diajukan oleh proses kriminal yang terbatas adalah pengakuan dan stigmatisasi kejahatan di masa lalu. Pengutukan terhadap kejahatan di masa lalu memiliki dimensi transformatif. Kejahatan yang secara terbuka diungkap dan dijelaskan penanggung-jawabnya, dapat mengisolasi pelakunya dan membebaskan masyarakat secara kolektif melalui proses transformasi yang terukur. Tindakan sederhana mengungkap kejahatan dapat menstigmatisasikan dan mendiskualifikasi mereka yang bertanggung-jawab dari lingkup publik dan privat, jabatan kepemimpinan politik atau semacamnya dalam rezim yang baru. Pengungkapan demikian secara tegas mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran ke dalam lingkup publik dan membebankan tanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa tersebut pada rezim pendahulu. Pada kondisi perubahan politik yang radikal, beberapa tujuan yang dicoba dicapai oleh proses pidana konvensional dapat dicapai dalam bentuknya yang lebih terbatas. Sanksi terbatas ini mencakup pula sanksi kemasyarakatan (civil sanction), yang dibicarakan lebih lanjut pada bab 5. Kegunaan sanksi terbatas memberikan pelajaran bagaimana tanggung jawab pidana dikonseptualkan dalam konteks transisional. Meskipun kita lazimnya menjustifikasi hukuman dengan merujuk tindakan yang dilakukan oleh tersangka pelakunya,92 dalam masa transisi, pertanyaannya adalah apakah ada teori tanggung jawab individual yang bisa menjembatani pergerakan dari rezim represif ke rezim yang lebih liberal. Sanksi transisional yang terbatas merupakan jembatan tersebut. Ketiadaan hukuman atau sanksi yang berat menunjukkan pemahaman yang lebih kompleks tentang tanggung jawab pidana dalam penerapan prinsip tanggung jawab individual dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kejahatan sistemik dalam pergeseran dari pemerintahan represif. Pengakuan terhadap batasan tanggung jawab individual didapatkan dengan peniadaan aspek penghukuman dalam proses. Penerimaan secara umum pengurangan atau peniadaan hukuman dalam masa-masa demikian menunjukkan pengakuan terhadap berkurangnya tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana yang terkait yang diasosiasikan dengan pemerintahan non-demokratik, dengan dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam transisi. Akhirnya, ketika institusi dan proses peradilan pidana tidak memiliki legitimasi yang biasanya dikaitkan dengan kedaulatan hukum, model pidana parsial paling tidak menunjukkan bahwa atribut-atribut kedaulatan hukum tetaplah berlaku. Sanksi terbatas memberikan solusi praktis terhadap dilema transisi yang ditimbulkan oleh penggunaan hukum pidana untuk mengadakan pergeseran normatif yang dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih liberal. 91 Lihat Sanford H. Kadish, “Foreword: The Criminal Law and the Luck of the Draw”, Journal of Criminal Law and Criminology 84 (musim dingin/semi 1994): 679, 698. 92 Lihat umumnya Hart, Punishment and Responsibility. 30 Amnesti Transisional Praktik-praktik yang dibicarakan di sini mengarah pada pemberian pengampunan dalam respon hukum pidana terhadap kejahatan negara dalam rezim lama. Bahkan, pembatasan proses pidana sering kali terlihat dalam pemberian amnesti umum terhadap kejahatan negara masa lalu: amnesti transisional. Bahkan, pergeseran politik kontemporer menunjukkan paling tidak pada suatu tingkat deskriptif, adanya kaitan antara transisi dan amnesti. Dilema tentang apakah perlu dilakukan penerapan hukum pidana tidak timbul dengan sendirinya, namun setelah perang, pertikaian internal, kediktatoran, atau pemerintahan represif lainnya, dan pada saat demikian, transisi sering kali timbul dari negosiasi, dan dalam konteks ini, peradilan pidana sering kali menjadi alat tawar-menawar, dengan kesepakatan untuk memberikan amnesti sebagai syarat untuk meliberalkan tatanan politik. Jadi, dari awal mula, amnesti memiliki peranan dalam mendorong transformasi politik. Dilema Perdamaian atau Keadilan Pertimbangkanlah bagaimana usaha pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi sesuai dengan usaha pencapaian keadilan. Bagaimana mendamaikan kedua tujuan tersebut?93 Dilema perdamaian atau keadilan memiliki banyak bentuk dalam transisi, baik dikaitkan dengan perang, konflik internal atau pergantian rezim. Mungkin contoh terjelas ketegangan yang ditimbulkan dari usaha untuk mencapai perdamaian atau keadilan tampak pada saat perang atau tepat setelah selesainya; selama masa permusuhan, sering kali terdapat pertentangan antara kedua tujuan tersebut, karena ancaman pertanggungjawaban pidana membayangi kelancaran pembicaraan perdamaian. Dilema ini tampak jelas dalam perdebatan historis Perang Dunia Kedua tentang persidangan penjahat perang yang kemudian akan diadakan di Nuremberg. Hal ini muncul lagi dalam perdebatan kontemporer tentang pengadilan kejahatan perang berkaitan dengan pertikaian di wilayah bekas Yugoslavia.94 Konflik Balkan secara lugas menunjukkan dilema yang timbul dalam pelaksanaan usaha-usaha untuk mencari keadilan dan perdamaian secara bersamaan. Misalnya, timbul masalah paradoksal untuk mengadili para pimpinan politik yang melakukan kejahatan perang sementara mereka adalah rekan dalam perundingan dalam kerangka PBB. Pertanyaan ini menjadi semakin penting dengan terbitnya tuduhan internasional terhadap pemimpin Serbia Bosnia, Radovan Karadzic, dan komandan militernya, Ratko Mladic, meskipun kerja sama mereka dalam perundingan perdamaian masih tetap diharapkan. Di satu pihak, keadilan tidak boleh mengalah pada politik, dan karena itu muncullah tuduhan tersebut, namun bila perundingan damai berakhir dengan amnesti, akan terdapat anggapan bahwa hal itu merupakan hasil politisasi. Contoh ini menggambarkan pandangan pro dan 93 Untuk diskusi tentang kaitan peradilan pidana internasional dengan perdamaian dalam konteks konflik Balkan, lihat Ruti Teitel, “Judgment at the Hague”, East European Constitutional Review 5, No. 4 (musim gugur 1996). 94 Lihat Elaine Sciolino, “U.S. Names Figures to Be Prosecuted over War Crimes”, New York Times, 17 Desember 1992, rubrik internasional; Roger Cohen, U.N. in Bosnia, Black Robes Clash with Blue Hats”, New York Times, 23 April 1995, hlm. A3. 31 kontra terhadap peradilan pidana dalam transisi. Jika penjahat perang bukanlah pihak yang sah dalam perundingan perdamaian, sejauh mana peradilan pidana dilaksanakan dalam masa perang? Sementara melanjutkan perundingan damai dengan tertuduh atau terdakwa penjahat perang di tengah-tengah dilaksanakannya usaha pencarian keadilan bisa dianggap sebagai usaha pembujukan politik. Sebaliknya, memulai proses pengadilan pada kondisi demikian bisa memberikan dampak buruk pada usaha pencapaian keadilan, menandakan standar hak asasi manusia yang rendah. Namun, tetaplah ada peran bagi keadilan dalam pertikaian, meskipun sering kali tidak dapat dikonkretkan. Pembicaraan saja tentang proses peradilan bisa berperan sebagai penggentar dalam konflik tertentu: misalnya, sidang Prancis mengenai pengadilan tentara Jerman pada masa Perang Dunia Pertama;95 demikian juga ancaman hukuman yang dikeluarkan pada masa Perang Dunia Kedua. Ketika pihak Sekutu menyadari adanya kekejaman, sebelum perang berakhir, Deklarasi Moskow memberikan peringatan bahwa Sekutu akan “mengejar mereka yang bersalah hingga ke ujung dunia dan menyeret mereka ke depan meja pengadilan”.96 Hingga sejauh mana peringatan keras ini memiliki nilai penggentar? Pertanyaan ini menjadi penting dalam ancaman pemberian hukuman yang lebih kontemporer di Balkan, karena tetap saja terjadi pelanggaran seperti pembantaian di Srebrenica. Ketika pertikaian hendak berakhir, hal lain dalam dilema perdamaian atau keadilan muncul pula. Terutama dalam “keadilan sang pemenang”, seperti pengadilan pasca-perang, sering diperlukan pengimbangan kepentingan perdamaian dan keadilan. Konflik antara kedua kepentingan itu tampak dalam tuntutan yang diformulasikan dalam pengadilan pasca-perang, seperti di Nuremberg, di mana individu dituduh bertanggung-jawab untuk melakukan pelanggaran “perang agresif”. Konsepsi dominan tentang pelanggaran pidana di Nuremberg dalam konteks perang atau damai menggarisbawahi sasaran ganda pengadilan tersebut untuk mencapai keadilan dan perdamaian.97 Namun, alih-alih penggunaan peradilan pidana untuk mecapai keadilan, jauh lebih banyak terlihat penggunaan pengampunan oleh kekuasaan pidana untuk memajukan transisi politik. Amnesti dalam Demokrasi Pengalaman historis maupun kontemporer menunjukkan kaitan erat antara amnesti dan transformasi liberal. Amnesti transisional sering mendahului, atau menyertai perubahan politik menuju ke arah liberal. Sebuah gambaran dari masa kuno tampak dalam konstitusi Athena tentang rekonsiliasi setelah kekalahan Athena dalam Perang Peloponesia. Pemerintahan oligarki transisional dan pengembalian demokrasi (meskipun bukan demokrasi dalam arti modern) menimbulkan pertanyaan tentang apakah, dan sejauh mana, perlu diadakan penghukuman terhadap rezim despotik sebelumnya. Peristiwa rekonsiliasi kuno ini dilaksanakan dengan kesepakatan berikut ini: “[T]idak seorang pun boleh mengingat pelanggaran masa lalu oleh siapa pun kecuali yang Tiga Puluh, Sepuluh, Sebelas dan para 95 Lihat Jacques Dumas, Les Sanctiones Penales des Crimes Allemands, Paris: Rousseau et cie., 1916. “The Moscow Declaration on German Atrocities, 1943”, dicetak ulang dalam Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 73. 97 Untuk tinjauan tentang usaha keras untuk mengajukan tuntutan tentang perang agresif, lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 37-39. 96 32 pemimpin Piraeus, dan bahkan tidak seorang pun dari mereka ini bila mereka berhasil dibawa ke tingkat penyelidikan.” Dalam contoh klasik ini, pergeseran dari peperangan dan pemerintahan tirani ke demokrasi dilakukan dalam amnesti luas, namun tidak universal. Terdapat batasan penting terhadap amnesti: “Pengadilan terhadap pembunuhan harus dilakukan sesuai dengan tradisi dalam kasus apabila seseorang telah membunuh atau melukai orang lain.”98 Dalam mengecualikan kasus yang memungkinkan pembalasan dendam, atas alasan pribadi atau keagamaan, parameter amnesti tersebut dibatasi pada kasus yang memiliki kaitan politik. Sebagaimana akan terlihat, syarat-syarat dalam amnesti kuno ini akan muncul kembali dalam amnesti hingga periode kontemporer – karena amnesti transisional, seperti pengadilan transisional, ditujukan untuk merespon dan menolak kebijakan politik rezim lama. Pada masa modern, mungkin kasus amnesti transisional yang paling menonjol adalah Spanyol pasca-Franco. Setelah masa pemerintahan fasis, Spanyol tidak melakukan pengadilan suksesor sama sekali, namun tetap berhasil mengkonsolidasikan pemerintahan demokratik: jadi, kebijakan amnesti Spanyol menjadi paradigma tentang potensi amnesti dalam transisi politik.99 “Membiarkan berlalu apa yang sudah berlalu” merupakan inti amnesti Spanyol: setelah masa pemerintahan otoriter selama empat puluh tahun, amnesti menjadi kesepakatan untuk melupakan masa lalu yang telah jauh. Amnesti tersebut diberikan secara luas dan umum bagi aktor negara dan non-negara, dalam pemerintahan kediktatoran dan perang saudara. Seperti pada transisi lebih awal di Eropa, di Amerika pada dekade 1980-an, semangat amnesti cukup kuat. Di berbagai negara di wilayah tersebut, Cili, Uruguay, El Salvador, Haiti dan Guatemala, amnesti terhadap pemerintahan militer yang represif merupakan pendahuluan terhadap perubahan politik, perdamaian dan rekonsiliasi. Amnesti Amerika Latin ini menunjukkan peran mereka dalam transisi yang dinegosiasikan.100 Janji pemberian amnesti terhadap pelanggaran masa lalu berhasil mengatasi kebuntuan politik dan memungkinkan liberalisasi.101 Jadi, misalnya, dalam transisi ternegosiasi di Uruguay, Haiti, El Salvador dan Guatemala, satu kartu penting dalam perundingan adalah janji untuk memberikan amnesti terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahan militer. Kekuasaan untuk mengadili dipertukarkan dengan perdamaian. Kesepakatan yang dicapai dengan junta 98 Lihat Aristoteles, The Athenian Constitution, diterjemahkan dengan pengantar dan catatan oleh P.J. Rhodes, Harmondsworth: Penguin, 1984, bab 34-41-1. 99 Lihat José Maria Maravall dan Julian Santamaria, “Political Change in Spain and the Prospects for Democracy”, dalam Guillermo O’Donnell et al. (eds.), Transition from Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991, 71-108. Lihat umumnya Raymond Carr dan Juan Pablo Aizpurtía, Spain: Dictatorship to Democracy, edisi kedua, London: Allen and Unwin, 1981. Untuk pembelaan terhadap amnesti Spanyol, lihat Fernando Rodrigo, “The Politics of Reconciliation in Spain’s Transition to Democracy” (makalah dipresentasikan pada Conference on Justice in Times of Transition, Salzburg, Maret 1993). 100 Tentang El Salvador dan Uruguay, lihat catatan kaki 103. Tentang Haiti, lihat Le Moniteur, Journal Offociel de la Republique d’Haiti Order (Arrète) of 2/6/90, yang memberikan amnesti total dan sepenuhnya kepada mereka yang antara 17 September 1988 dan 7 Februari 1990 terlibat dalam kejahatan dan pelanggaran terhadap keamanan nasional. Tentang amnesti Kolombia, lihat Javier Correa, “La Historia de las Amnistias y los Indultos: Volver a Empezar”, dalam Los Cominos de la Guerra y la Paz, Vol. 1 La Reinsercìon, Bogotá: Fondo Editorial Para la Paz, 1990. 101 Lihat Howard W. French, “In Salvador, Amnesty vs. Punishment”, New York Times, 16 Maret 1993, rubrik internasional; Howard W. French, “Offer of Amnesty Removes Obstacle to Accord in Haiti”, New York Times, 14 April 1993, rubrik internasional. 33 dibayar dengan amnesti umum. Setelah kesepakatan tersebut dicapai, timbul perdebatan tentang lingkup amnesti yang akan diundang-undangkan.102 Dalam proses perundingan perdamaian El Salvador yang diadakan di bawah lindungan PBB, meskipun amnesti tidak secara eksplisit dimuat dalam kesepakatan damai, seminggu setelah kesepakatan ditandatangani, pada tanggal 16 Januari 1992, Undang-Undang Rekonsiliasi Nasional disahkan. Singkatnya jarak waktu tersebut menandakan bahwa amnesti disepakati secara diam-diam dalam proses perdamaian.103 Kesepakatan serupa memungkinkan transisi di Uruguay, di mana langkah-langkah amnesti dilaksanakan dalam beberapa tahap. Naval Club Pact, yang memberikan amnesti bagi para penanggung-jawab pelanggaran hak asasi manusia, disepakati oleh anggota perwakilan politik negara itu dalam negosiasi mengenai syarat transisi ke pemerintahan sipil. Kesepakatan ini kemudian diratifikasi oleh parlemen dalam Undang-Undang Perdamaian Nasional, yang disahkan pada tahun 1986. Akhirnya, empat tahun kemudian, Undang-Undang yang Menghapuskan Klaim Negara untuk Menghukum Kejahatan Tertentu, yang jauh lebih luas, diajukan untuk diadakan referendum.104 Amnesti hasil kesepakatan seperti ini, yang merupakan hasil negosiasi transisi, menunjukkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam usaha pencapaian keadilan melalui pemidanaan. Dalam transisi ternegosiasi, baik wakil militer maupun oposisi politik yang terlibat dalam konflik sama-sama memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan kekebalan dari pengadilan. Di negara-negara lain di wilayah ini, bentuk-bentuk pemgampunan lain diberikan bersama dengan transisi. Meskipun pada awalnya terdapat pengadilan terhadap junta di Argentina, sejumlah undang-undang menghentikan proses tersebut.105 102 Lihat “The Deal: Amnesty Law Expected to Clear Junta Very Soon”, New York Times, 21 September 1994, hal. A17. 103 Keputusan legislatif No. 486, 3/22/93, El Salvador (22 Maret 1993), menyetujui Undang-Undang Amnesti Umum untuk Konsolidasi Perdamaian. Lihat Todd Howland, “Salvador Peace Starts with Misstep”, Christian Science Monitor, 7 Februari 1992. John J. Moore Jr., “Problems with Forgiveness: Granting Amnesty under the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador”, Stanford Law Review 43 (1991): 733. “Ley de Reconciliacion Nacional” (Undang-undang Rekonsiliasi Nasional), Keputusan No. 145-96 tertanggal 23 Desember 1996, dicetak ulang dalam Guatemala Constitutional Court Decision on Amnesty, Nos. 8-97 and 20-97, at. 19-20 (7 Oktober 1997), instrumen dasar untuk rekonsiliasi dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan menghapuskan semua tanggung jawab pidana bagi kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam konflik bersenjata; dan menghapuskan tanggung jawab untuk kejahatan lainnya, terkecuali genosida, penyiksaan, atau penghilangan paksa. 104 Lihat Law No. 15.848 (Uruguay), “Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado (Undang-Undang yang Menghapuskan Klaim Negara untuk Menghukum Kejahatan Tertentu), Pasal 1. Disepakati bahwa, sebagai konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang timbul dari persetujuan antara partai-partai politik dan angkatan bersenjata yang ditandatangani pada bulan Agustus 1984, dan untuk menyelesaikan transisi ke tatanan konstitusional sepenuhnya, negara mencabut haknya untuk memidana kejahatan-kejahatan yang dilakukan hingga tanggal 1 Maret 1985, oleh anggota militer atau polisi atas alasan politik atau memenuhi tugas dan menaati perintah dari atasan selama masa de facto; Americas Watch, Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and the Referendum Campaign in Uruguay, New York: Human Rights Watch, 1990. Lihat juga Shirley Christian, “Uruguay Votes to Retain Amnesty for the Military, New York Times, 17 April 1989, rubrik internasional, hlm. A8; Martin Weinstein, Uruguay-Democracy at the Crossroads, Boulder: Westview Press, 1984. 105 Lihat Due Obedience Law; Law No. 23.049 (Argentina, 1984). The Full Stop Law; Law No. 23.492, diberlakukan pada tanggal 24 Desember 1986, dan Due Obedience Law; Law No. 23.523, diberlakukan pada tanggal 8 Juni 1987. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, melalui keputusan presiden, Pardon No. 1002 (7 Oktober 1989) memerintahkan bahwa semua proses hukum yang dijalankan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dihentikan. 34 Perundingan amnesti transisional sering kali dilakukan untuk menstabilkan dan memantapkan transisi. Namun, hal ini memiliki arti paradoks, yaitu bahwa amnesti disyaratkan oleh kepentingan politis masyarakat yang mengalami transisi. Dengan demikian tampak bahwa syarat-syarat untuk tidak mengadakan pengadilan sering kali tidak berbeda dari syarat-syarat untuk mengadakan pengadilan pula. Amnesti, terutama bila diberikan secara bersyarat dan individual, dapat berfungsi mirip hukuman. Peniadaan pengadilan, seperti juga ancaman pengadilan, dapat menjadi aturan politik transisional yang efektif. Misalnya, setelah Perang Saudara Amerika, amnesti diberikan dengan syarat bahwa Konfederasi tetap setia kepada persatuan.106 Di Afrika Selatan, kesepakatan untuk menghentikan pemerintahan apartheid menjadi syarat bagi amnesti untuk pelanggaran “politik” dalam pemerintahan sebelumnya.107 Promotion of National Unity and Reconciliation Bill memberikan amnesti dengan syarat pengakuan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Tujuan eksplisitnya adalah persatuan masyarakat. Harga yang harus dibayar tersebut mencerminkan karakter politis dan instrumental dari amnesti transisional dan kaitannya dengan rekonsiliasi masyarakat, demikian pula pengembalian ketaatan pada kedaulatan hukum. Pada masa gejolak, pertimbangan peradilan pidana merupakan bagian dari perhitungan politik yang lebih luas. Memberikan hak-hak politik bagi para pelaku pelanggaran sebagai pertukaran terhadap dukungan bagi persatuan yang baru dan stabilitas politik mencerminkan sasaran konvensional pemberian hukuman untuk menjamin keberlangsungan kedaulatan hukum. Dengan demikian amnesti dapat memajukan sasaran normatif dalam transisi politik. Keadilan, Pengampunan, Politik dan Kedaulatan hukum Penghukuman atau impunitas? Kembali ke perdebatan awal dalam bab ini, peran penting amnesti dalam transisi mengarah ke pertanyaan lebih luas tentang kaitan pengampunan terhadap kedaulatan hukum, terutama dalam masa transisi. “Pengampunan” (clemency) memiliki arti yang luas, termasuk amnesti dan pemaafan (pardon). Meskipun ada yang membedakan istilah-istilah tersebut karena konotasinya, atau waktu pemberiannya (setelah atau sebelum keputusan), istilah tersebut biasanya sering dipertukarkan penggunaannya. Amnesti transisional memberikan tantangan sulit sebagaimana telah diklaim di awal bab ini, yaitu bahwa pemberian hukuman mutlak diperlukan untuk konsolidasi demokratik. Menurut argumen yang berkeras untuk memberikan hukuman, dikatakan bahwa revolusi yang baik 106 Lihat umumnya Jonathan Truman Dorris, Pardon and Amnesty under Lincoln and Johnson: The Restoration of the Confederates to Their Rights and Privileges, 1861-1898, Westport, Conn: Greenwood Press [1953], 1977. 107 Lihat Konstitusi Sementara Afrika Selatan (1993) Epilogue on National Unity and Reconsiliation. Lihat § 20(2)(c) Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, seperti diperbaiki dalam Promotion of National Unity and Reconciliation Act 87 of 1995. Komisi harus memutuskan apakah suatu pelanggaran tertentu dapat dikaitkan dengan sasaran politik sesuai definisi dengan dasar apakah pelanggaran tersebut disarankan, direncanakan, diarahkan, diperintahkan, atau dilakukan di Afrika Selatan antara bulan Maret 1960 hingga Desember 1994, oleh atau atas nama organisasi politik yang dikenal secara publik, gerakan pembebasan, agen negara atau anggota pasukan keamanan, dan dengan melihat pada kriteria khusus yang dijabarkan dalam Reconciliation Act. Kriteria tersebut mencakup penyidikan terhadap motif, konteks, bobot dan tujuan dilakukannya pelanggaran, apakah pelanggaran tersebuit dilakukan atas perintah langsung atau persetujuan, dan apakah pelanggaran tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau “masalah pribadi, permusuhan atau rasa benci terhadap korban”, § 20(3)(f)(ii). Lihat umumnya Allister Sparks, Tommorow is Another Country: The Inside Story of South Africa’s Road to Change, New York: Hill and Wang, 1995. 35 tidaklah berakhir dengan amnesti, karena kegagalan suatu masyarakat untuk menuntut tanggung jawab dari para pelaku pelanggaran adalah kelanjutan dari praktik “impunitas” di masa lalu, dan menggagalkan proses liberalisasi.108 Impunitas ini tetap berlanjut dalam transisi antar-rezim, kecuali dihentikan dengan pemberian hukuman. Bentuk keadilan ini dikatakan mutlak diperlukan untuk pengembalian kedaulatan hukum. Menurut argumen ini, amnesti transisional merupakan “penjualan” keadilan kepada kepentingan politik sementara, yang pada ujungnya merugikan prospek demokrasi. Namun terdapat pula argumen kebalikannya: pembatasan kekuasaan penghukuman, yang menandakan kembalinya ketaatan pada kedaulatan hukum.109 Dalam hal ini, klaim normatif tersebut tampaknya terlalu dipaksakan kaitannya dengan realitas. Pengamatan bahwa praktik amnesti dikaitkan secara de facto dengan transisi dianggap sebagai kaitan antara pernyataan normatif tentang penggunaan kekuasaan pengampunan dan kedaulatan hukum yang liberal. Ketika permasalahan amnesti diperdebatkan dalam konteks utamanya yakni transisi, tantangan-tantangan terhadap amnesti transisional mengasumsikan bahwa penangguhan kekuasaan penuntutan melanggar inti kedaulatan hukum yang terkait dengan demokrasi mapan. Namun, pembatasan penggunaan kekuasaan pidana tidaklah terbatas pada masa transisi saja. Yang kurang jelas adalah di mana letak posisi amnesti transisional dalam pandangan kita tentang pemberian pengampunan pada umumnya? Apa standar yang relevan? Siapa yang berhak memberikan amnesti? Dengan prinsip apa? Hak dan kewajiban apa saja yang terkait? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan titik awal untuk mengevaluasi amnesti transisional. Pertimbangkanlah argumen hukum internasional untuk memberikan hukuman, yaitu bahwa kewajiban untuk menghukum dianggap berasal dari berbagai norma konvensional dan kebiasaan.110 Namun, skema remedial hukum internasional, yang dibentuk dalam kerangka hak-hak individual, tidak mengkonstruksi hukuman sebagai hak yang akan memberikan kewajiban untuk dilaksanakan oleh negara. Dan, bahkan apabila argumen tersebut didasarkan pada analogi dengan negara demokrasi mapan, penggunaan hukuman, seperti akan dibicarakan di bawah, tetaplah digunakan dengan kehati-hatian dalam hampir semua sistem hukum. Dalam sistem hukum internasional, konvensi-konvensi tersebut pun dianggap sudah cukup terpenuhi dengan tindakan remedial selain hukuman. Dalam keputusan penting yang meninjau kasus impunitas di Amerika Latin, Pengadilan Inter-Amerika memutuskan bahwa kewajiban untuk melindungi warga negara dari penindasan dapat dilaksanakan dengan tindakan remedial lain, seperti penyelidikan dan pemberian ganti rugi.111 Namun, dalam keputusan lain yang mengevaluasi hukum amnesti Argentina dan Uruguay, Komisi Hak Asasi Manusia InterAmerika memutuskan bahwa amnesti terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia melanggar berbagai kewajiban negara menurut Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika untuk 108 Untuk argumen utama yang menentang amnesti yang menyertai gelombang transisi kontemporer ini, lihat Aryeh Neier, “What Sould Be Done about the Guilty”? New York Review of Books, 1 Februari 1990, hlm. 32. 109 Lihat Stephen Holmes, “Making Sense of Postcommunism” (rancangan untuk New York University Program for the Study of Law, Philosophy and Social Theory), 10-13; Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991. 110 Lihat Orentlicher, “Settling Accounts”, 2537; Naomi Roth-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law”, California Law Review 78 (1990): 449. 111 Lihat Velásques-Rodrígues Judgment, Inter-Am. Ct. H.R., Ser. C., No. 4 (1988). 36 melindungi dan menjamin hak asasi manusia, dan juga hak para korban untuk menuntut keadilan.112 Di luar argumen hukum internasional tentang kewajiban untuk menghukum adalah argumen tradisional menurut sistem hukum negara-negara demokrasi mapan. Namun, seperti akan dibicarakan di bawah, argumen-argumen tersebut tidaklah memberikan kewajiban untuk menghukum dalam transisi, namun memang memberikan dasar yang baik untuk mengevaluasi amnesti transisional. Seperti tampak jelas, bahkan dalam kondisi normal, kedaulatan hukum tidaklah berarti penerapan peradilan pidana secara mutlak, dan alasan-alasan untuk memberikan pengampunan, seperti juga dalam masa transisi, sering kali bersifat politis. Argumen retributif untuk memberikan hukuman bukanlah demi kepentingan masyarakat di masa depan, melainkan dengan memperhatikan pertimbangan moral yang terkait dalam tindakan-tindakan yang terkait. Sebuah tulisan yang terkenal dari Immanuel Kant berhipotesis tentang masyarakat di pulau gersang yang hendak membubarkan diri, yang sedang mempertimbangkan apakah akan memberikan hukuman, dan apakah masyarakat itu memiliki kewajiban untuk menghukum “semua orang yang pernah membunuh” sehingga “semua orang akan ... mendapatkan upahnya sesuai dengan tindakannya dan dengan demikian ... hutang darah tidak akan mengotori masyarakat tersebut.”113 Bahkan masyarakat yang akan bubar pun memiliki kewajiban untuk membebankan pertanggungjawaban individual, untuk menghilangkan tanggung jawab moral dari seluruh masyarakat luas. Klaim Kantian untuk memberikan hukuman dalam masyarakat yang akan bubar ini menguji justifikasi untuk memberikan hukuman dalam konteks di mana tidak terdapat tujuan kepentingan masa depan yang ditekankan bila terdapat kontinuitas sosial, yang tampak dalam kondisi transisional. Dari perspektif retributif, tidak menghukum berarti masyarakat menanggung tanggung jawab kolektif, dengan konsekuensi legitimasi institusi peradilannya. Peradilan pidana memainkan peranan tidak hanya dalam menggariskan tanggung jawab individual dan kolektif, namun juga melegitimasikan institusi peradilan; dengan demikian ia menarik garis antara dua rezim. Membebankan tanggung jawab individual akan mengangkat tanggung jawab kolektif dari rezim lama dan melegitimasi kembali otoritas negara. Sementara argumen retributif memiliki klaim yang kuat tentang kewajiban untuk menghukum, ia tidak menjelaskan dengan baik pandangan tentang peran hukuman dalam sistem hukum, baik dalam masa biasa maupun masa transisi.114 Pemahaman tentang kaitan antara hukuman dengan kedaulatan hukum bervariasi secara luas dalam berbagai budaya hukum. Dalam sistem civil law, prinsip legalitas menuntut adanya penerapan hukuman secara nyaris mutlak. Namun, dalam sistem common law, anggapan tentang legalitas ini tidak sama: norma mendasarnya adalah kekuasaan penuntutan yang tidak diterapkan pada kekuatan 112 Lihat Report No. 28/92, Cases 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309, 10.311, Argentina’s Annual Report of the Inter-American Commision of Human Rights 1992-1993, 41b, OAS doc. OES/Ser.4L/UV/II.83/doc. 14/Corr. 1 (1993). Lihat juga Robert Goldman, “Amnesty Laws, International Laws, and the American Convention on Human Rights”, The Law Group Docket 6, no. 1 (1989): 1. 113 Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terjemahan Mary Gregor, New York: Cambridge University Press, 1991, 183. 114 Lihat Teitel, “How are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” Namun ada pula pakar yang mendasarkan justifikasi untuk kebijakan pengampunan dengan pertimbangan retributif yang berdasar pada ketiadaan hukuman. Lihat Katherine Dean Moore, Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest, New York: Oxford University Press, 1989. 37 sepenuhnya, dan keadilan dalam sistem ini ditinjau dari perhatian spesifik terhadap kasuskasus.115 Dengan demikian, pengampunan pada masa normal bisa menjadi titik awal untuk menilai amnesti transisional. Pengampunan dalam masa biasa memiliki keserupaan dengan amnesti transisional dalam sifat politisnya. Di negara-negara demokratis, pengampunan atau amnesti (seperti amnesti legislatif atau pajak) biasanya dikaitkan dengan perpindahan kekuasaan politik dalam pergantian administratif yang biasa. Ini menunjukkan analogi antara perubahan administratif biasa dan pergantian rezim politik dalam transisi. Amnesti, seperti juga hukuman, adalah praktik yang menunjukkan kedaulatan – menunjukkan siapa pemegang kekuasaan politik. Dengan demikian, penangguhan hukuman, seperti juga penjatuhannya, mendefinisikan transisi politik. Sifat dan peran politis yang penting dari pengampunan diakui dan bahkan didefinisikan oleh pemisahan kekuasaan secara institusional, misalnya, pemisahan kekuasaan pengampunan dari kekuasaan kehakiman. Pada masa biasa, para aktor politik memegang kekuasaan pengampunan. Dalam sistem konstitusi Amerika, misalnya, kekuasaan pengampunan, yang mengikuti kepemilikan kekuasaan serupa oleh raja, dipegang oleh eksekutif.116 Bahwa kekuasaan pengampunan tidak berada pada badan yudikatif, namun pada eksekutif, yang diberikan dengan dasar kasus demi kasus dan dipertimbangkan secara spesifik, menunjukkan sifatnya yang politis. Pemisahan kekuasaan penghukuman dan pengampunan tidak hanya terdapat pada sistem hukum Anglo-Amerika. Dalam sistem konstitusional Amerika Latin, diferensiasi kekuasaan tersebut lebih tampak lagi. Dalam sistem hukum Amerika Utara, kekuasaan untuk menuntut dan mengampuni berada pada eksekutif dan berkaitan dengan kepentingan kebijakan; dalam sistem Amerika Latin, kekuasaan untuk menuntut berada pada badan peradilan, sementara kekuasaan untuk mengampuni berada pada eksekutif.117 Pemisahan kedua kekuasaan ini menekankan fungsi politik pengampunan. Tatanan institusional negara demokrasi mapan menunjukkan usaha untuk memisahkan proses peradilan dan pengampunan. Sementara keadilan adalah wilayah kekuasaan pengadilan dan diterapkan berdasar standar dan justifikasi prinsip-prinsip konstitusional, pengampunan termasuk dalam wilayah kekuasaan cabang-cabang politik yang digunakan untuk memajukan kepentingan politik,118 dan secara eksplisit dijustifikasi dalam kerangka transisi, seperti perdamaian dan rekonsiliasi.119 Bahkan meskipun pengampunan dianggap sebagai bagian integral kedaulatan hukum dalam masa normal, terdapat pula perbedaannya yang signifikan dengan pelaksanaannya pada masa perubahan politik Terdapat frekuensi pemberian amnesti yang lebih tinggi, bersamaan dengan pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan untuk memberikan sanksi pidana. Setelah 115 Lihat John Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Tradition of Western Europe and Latin America, Stanford: Stanford University Press, 1985; William T. Pizzi, “Understanding Prosecutorial Discretion in the United States: The Limits of Comparative Criminal Procedure as an Instrument of Reform”, Ohio State Law Journal 54 (1993): 1325. 116 Lihat Moore, Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest 790-86; “The Conditional Presiden Pardon”, Stanford Law Review 28 (1975): 149; Daniel T. Kobil, “The Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from the King”, Texas Law Review 69 (1991): 569. 117 Lihat Irwin P. Stotzky (ed.), Transition to Democracy in Latin Amerikca: The Role of the Judiciary, Boulder: Westview Press, 1993. 118 Lihat Jeffrie G. Murphy dan Jean Hampton, Forgiveness and Mercy, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 162-86 (tentang sifat dan kaitan pengampunan dengan keadilan). 119 Sebagai contoh, pengampunan kepresidenan Argentina dijustifikasi dengan kepentingan “harmoni sosial” yang jelas-jelas politis. 38 pemerintahan yang represif, amnesti transisional menimbulkan masalah struktural tentang pelanggaran-pelanggaran di mana negara memiliki andil besar. Timbul pertanyaan: apakah adil bagi suatu pemerintahan, bahkan rezim yang baru, untuk menggunakan kekuasaan penghukuman atau pengampunan. Suatu variasi dalam masalah ini tampak dalam tulisan John Locke dan Kant abad ke-18, yang menolak pengampunan, karena penyalahgunaannya dalam pemerintahan monarki. Sementara dalam keadaan alami (state of nature), hak untuk memberikan hukuman (dan untuk tidak menghukum) ada pada komunitas, kontrak sosial mengalihkan hak tersebut kepada pemegang kedaulatan. Pada demokrasi mapan, kekuasaan pengampunan biasanya dipegang oleh pemegang kedaulatan, namun pada saat krisis politik, kekuasaan tersebut tampaknya diambil alih kembali oleh warga negara.120 Jadi, setelah Revolusi Prancis, kekuasaan pengampunan ditangguhkan, karena ia dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan oleh raja secara sewenang-wenang dan tidak sah. Dalam contoh lain, terbatasnya kekuasaan pengampunan dalam eksekutif Amerika121 secara gamblang menggambarkan transisionalitas dalam definisi konstitusional terhadap kekuasaan untuk memberikan amnesti dan batasan-batasannya yang ditentukan dari pengalaman sejarah penggunaannya. Peninggalan sejarah represi di masa lalu membantu membentuk otoritas negara terhadap kekuasaan penghukuman dan pengampunan. Bahkan, hal di atas menunjukkan bahwa ketiadaan legitimasi dalam institusi mempengaruhi syarat untuk pelaksanaan baik penghukuman maupun pengampunan dalam transisi. Sejumlah besar pemberian amnesti dalam masa transisi menunjukkan bahwa kontinuitas institusional dalam bentuk apa pun dari pemerintahan represif di masa lalu ke pemerintahan yang baru akan melemahkan otoritas rezim penerus untuk melakukan proses pengadilan. Pelaksanaan kekuasaan penghukuman oleh rezim penerus sering kali dianggap sebagai kelanjutan kebijakan politis dari masa pemerintahan non-liberal. Bila pergantian rezim tidak berlangsung bersama dengan reformasi peradilan, pengadilan suksesor dilemahkan dengan “tu quoque” (tangan kotor). Sifat luar biasa dari peradilan suksesor menunjukkan kondisi peradilan yang terkompromi dalam masa transisi, berkaitan dengan keterlibatan negara dalam kejahatankejahatan yang terkait, berkaitan dengan keterlibatan negara dalam kejahatan-kejahatan yang terkait, dan ketiadaan institusi peradilan yang benar-benar sah. Pengakuan bahwa hal-hal tersebut merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan mungkin bisa menjelaskan banyaknya amnesti di Amerika Latin, karena di wilayah ini, badan peradilan amat tercemar oleh keterlibatannya dalam represi di masa lalu, dan tidak mengalami reformasi setelah transisi. Dalam kondisi demikian, institusi peradilan tidak memiliki legitimasi, dengan konsekuensi yang buruk bagi keabsahan hukuman yang diberikannya. Dalam konteks ini, pemberian pengampunan mungkin memiliki legitimasi yang lebih besar, terutama bila diberikan oleh aktor-aktor politik yang baru dipilih, seperti eksekutif atau legislatif. Jadi, banyaknya amnesti dalam kondisi transisional menunjukkan sesuatu yang penting tentang kedaulatan hukum yang menjadi prasyarat pemberian hukuman secara sah. Kaitan erat antara hukuman dan amnesti tampak dalam parameter amnesti transisional yang mencakup kejahatan politik, yang menjadi batasan pemberian hukuman secara sah dalam 120 Lihat A. John Simmons, “Locke and the Right to Punish”, Philosophy and Public Affairs 20 (1991): 319. Lihat Alexander Hamilton, The Federalist No. 69, ed. Jacob E. Cooke, Middletown, Conn: Wesleyan University Press (merasionalisasi kekuasaan pengampunan eksekutif yang membandingkannya dengan kekuasaan raja). 121 39 masa transisi. Transisi politik menjadi prinsip penentu amnesti. Misalnya, hukum amnesti El Salvador mencakup “tidakan-tindakan termasuk kejahatan politik atau kejahatan dengan konsekuensi politik atau kejahatan biasa yang dilakukan oleh tidak kurang dari dua puluh orang”.122 Promotion of National Unity and Reconciliation Bill Afrika Selatan mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diberikan amnesti sebagai berikut, “tindakan yang dikaitkan dengan sasaran politik”. Amnesti transisional pada garis politik memiliki risiko serupa dengan yang dijelaskan pada awal bab ini – hantu keadilan yang dipolitisasi. Sebagaimana kebijakan penghukuman memiliki risiko menjadi bagian dari siklus mengalihkan tanggung jawab tentang kesalahan, kebijakan pengampunan atas dasar politik pun demikian. Baik hukuman maupun amnesti dapat berperan secara konstruktif dalam mendefinisikan transisi politik. Namun ada pula batasan kedaulatan hukum dalam praktik amnesti transisional, prinsip-prinsip penting tentang pelaksanaan kekuasaan pengampunan secara sah. Beberapa dari batasan tersebut berkaitan dengan prosedurnya. Amnesti-diri sendiri, yaitu yang diberikan oleh rezim pendahulu, seperti oleh militer Argentina, pada umumnya dianggap tidak sah dan dibatalkan dalam transisi.123 Lebih lanjut lagi, baik hukuman maupun amnesti harus mengikuti prosedur biasa dan dilegitimasi oleh publik. Amnesti “demokratis”, yaitu yang dipertimbangkan oleh masyarakat dan disepakatai melalui konsensus, mencerminkan usaha untuk melegitimasi pemberian pengampunan dalam transisi. Prototipe klasik amnesti demokratis berasal dari Athena Kuno, di mana pengampunan diputuskan melalui pemungutan suara,124 melalui proses “adeia” yang membutuhkan dukungan enam ribu orang sebelum pengampunan disepakati. Setelah perang saudara di Athena, amnesti pada tahun 403 S.M. disahkan melalui suara mayoritas dan diberikan kepada semua orang yang terlibat dalam perang saudara. Amnesti transisional sering kali dinegosiasikan oleh wakilwakil dari rezim lama dan oposisi. Meskipun kesepakatan amnesti bisa disusun melalui proses tawar menawar dan non-legislatif, ia harus disahkan melalui proses yang lebih partisipatoris selama masa transisi. Dalam transisi kontemporer, seperti juga di Athena kuno, plebisit dan pelaksanaan kedaulatan langsung memberikan keabsahan bagi amnesti transisional. Melalui proses demokratik, amnesti memiliki pertanggungjawaban politik; prosesproses politik yang menyertai amnesti legislatif, yang memungkinkan pertimbangan secara luas tentang sifat dan sigifikansi kejahatan negara di masa lalu. Misalnya proses referendum di Uruguay, juga proses persidangan parlementer di Afrika Selatan.125 Proses pertimbangan amnesti ini sendiri memiliki andil terhadap kepentingan hukum dalam proses transisi, karena dalam perdebatan yang ada, sering kali diadakan kesaksian dan dengar pendapat tentang temuan-temuan yang berkaitan dengan pelanggaran di masa lalu. Proses demokratik ini berarti bahwa mereka lebih transparan dan dipertimbangkan secara lebih matang daripada hukum 122 Decision on the Amnesty Law, Proceedings No. 10-93, El Salvador, Supreme Court of Justice, 1993. Lihat Law No. 23.040 (27 Desember 1983) (membatalkan Law No. 22.924 karena inkonstitusional). 124 Lihat Aristoteles, The Athenian Constitution; Martin Oswald, From Popular Souvereignty to the Souvereignty of the Law: Law, Society, and Politics in Fifth Century Athens, Berkley: University of California Press, 1986; Thomas Clark Loening, The Reconciliation Agreement of 403/402 BC in Athens, Its Content and Aplication, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1987. 125 Tentang perdebatan Uruguay mengenai “Ley de Caducidad” lihat Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and the Referendum Campaign in Uruguay, An Americas Watch Report, Americas Watch Commitee, 1989, 15-16. Di Afrika Selatan, perdebatan amnesti menjadi bagian perdebatan parlementer tentang pengesahan konstitusi 1993 negara tersebut. Lihat Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, Juta’s Statutes of the Republic of South Africa, vol. 1 (1997). 123 40 konvensional. Jadi, bahkan tidak memberikan hukuman bisa mencapai sasaran-sasaran transisional, seperti klarifikasi dan pengutukan kesalahan-kesalahan rezim lama. Amnesti transisional dibentuk oleh kedaulatan hukum dengan cara-cara lainnya. Selain batasan prosedural di atas, baik dalam pelaksanaan penghukuman maupun tidak melakukan penghukuman, terdapat komitmen terhadap perlindungan setara oleh hukum. Prinsip perlindungan setara secara konstitusional memberikan batasan pada amnesti-amnesti, bahkan yang diberikan dengan alasan politis. Perlindungan setara berarti perlakuan yang sama dalam kasus-kasus serupa, dan tidak menggunakan dasar yang tidak dapat dijustifikasi, seperti ras, agama, atau klasifikasi serupa, sehingga bukanlah hal yang kontroversial bahwa kategorikategori demikian tidak menjadi dasar untuk pemberian atau penolakan pengampunan.126 Perlindungan konstitusional setara memberikan batasan lebih lanjut terhadap politisasi peradilan pidana. Sementara politik merupakan dasar yang diperbolehkan untuk memberikan pengampunan, terdapat batasan terhadap pemberian amnesti atas dasar pandangan politik, sehingga mencegah pemberian amnesti atas dasar politik partisan. Sementara pemberian amnesti kepada semua pihak akan berarti memberikan amnesti kepada lebih banyak orang, ia memajukan kedaulatan hukum dan legitimasi dalam pemberian pengampunan. Dalam argumen mendasar untuk memberikan hukuman dalam transisi, amnesti sering kali dikatakan menunda proses pengembalian kedaulatan hukum. Namun, seperti dibicarakan di atas, bahkan pada sistem demokrasi yang stabil, kekuasaan peradilan pidana tidak diterapkan pada kekuatannya yang maksimal. Tentu saja, dalam negara demokrasi mapan, praktik pengampunan dilakukan dalam konteks ketaatan terhadap kedaulatan hukum secara lebih luas; sementara amnesti transisional dilakukan setelah masa-masa hukum diabaikan secara luas. Namun, amnesti transisional harus dievaluasi berdasarkan konteks kedaulatan hukum luar biasa dalam kondisi peradilan transisional, di mana institusi peradilan masih terkompromi. Amnesti transisional memiliki legitimasi terkuat bila dihasilkan dari proses demokratik, seperti referendum langsung. Pengambilan kebijakan amnesti tidak berarti melupakan kesalahan di masa lalu, seperti sering kali disyaratkan oleh penyidikan kasus demi kasus seperti dalam proses pidana. Baik penghukuman maupun amnesti memiliki peran sistemik dalam konstruksi transisi politik. Pada akhirnya, amnesti dan hukuman adalah dua sisi dari mata uang yang sama: ritus legal yang secara terbuka dan kuat menunjukkan perubahan kedaulatan yang ada dalam transisi politik.127 Praktik amnesti dan penghukuman transisional memainkan peran penting dalam konstruksi periode politik tersebut. Baik penghukuman maupun amnesti membantu mendefinisikan pergeseran rezim, karena dengan menunjukkan pelanggaran di masa lalu mereka membantu mengkonstruksikan sejarah politik. Praktik-praktik transisional ini mendefinisikan batasan politik: diskontinuitas dalam transisi – “sebelum dan sesudah”, dan juga berperan dalam menunjukkan kontinuitas dalam transisi. Batasan Pengampunan di Negara Liberal: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Suatu batasan terhadap kekuasaan politik untuk mencegah penghukuman dalam negara yang sedang menuju demokrasi adalah “kejahatan terhadap kemanusiaan”, karena pelanggaran ini 126 Lihat Bordenkircher v. Hayes, 434 US 357, 364 (1978). Untuk pandangan terkait tentang alternasi ritual, lihat René Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977. 127 41 tidak memiliki parameter jurisdiksi konvensional. Ajudikasi untuk kejahatan terhadap kemanusiaan membatasi dan mengutuk praktik penindasan politik oleh negara yang lama, suatu batasan yang tampaknya kebal terhadap politik nasional. Dengan demikian, pengadilan terhadap pelanggaran ini memiliki kekuatan sebagai berlakunya kedaulatan hukum. Hal ini tampak dalam usaha untuk memasukkan respon hukum transisional ke dalam pengadilan pidana internasional yang permanen. Pendefinisian kejahatan terhadap kemanusiaan ini mengkonstruksikan norma-norma konstitusional yang menjadi inti kedaulatan hukum. Ia membedakan negara yang sedang menuju demokrasi dengan negara-negara non-demokratik. Di sini tampak potensi normatif terbesar peradilan transisional. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk penindasan yang paling buruk, yang melampaui batas-batas nasional dan merupakan pelanggaran terhadap seluruh masyarakat internasional. Dikodifikasi untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua melalui Piagam Nuremberg, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai pelanggaran berat, seperti pembunuhan, pengusiran paksa dan penyiksaan, yang diadakan pada saat peperangan terhadap warga sipil, dan juga “penindasan atas dasar politis, rasial atau keagamaan”.128 Melampaui kejahatan perang, piagam Nuremberg memiliki jurisdiksi terhadap penindasan yang dilakukan negara terhadap warganya sendiri. Pelanggaran demikian dianggap melampaui batas-batas hukum nasional dan melanggar hukum semua negara, dan dengan demikian dapat diadili oleh sebuah tribunal internasional. Namun, meskipun terdapat konsensus tentang jurisdiksi internasional, karena pada waktu itu prinsip tersebut masih merupakan hal yang baru dan terdapat kecemasan tentang retroaktivitas, pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan dibatasi pada kejahatan yang terkait dengan perang. Jadi, meskipun secara formal merupakan tuntutan yang terpisah, kejahatan terhadap kemanusiaan digabungkan dengan kejahatan perang lainnya.129 Arti sentral kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai “pelanggaran yang mempengaruhi seluruh umat manusia” tampak jelas ketika respon terhadap kekejaman negara melintasi batas negara ke arena internasional. Sejarahnya ini dimulai sejak sebelum proses pasca-perang. Protes dan intervensi internasional muncul, misalnya, setelah perang YunaniTurki pada tahun 1827, dan pada awal dekade 1900-an, “atas nama kemanusiaan” terhadap penindasan di Rumania dan Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, sebuah komisi bersidang tentang metode peperangan, yang menentukan pelanggaran terhadap “hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dan hukum-hukum kemanusiaan yang mendasar” dan “memperingatkan” bahwa semua orang dari negara-negara musuh yang bersalah atas pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang atau hukum kemanusiaan dapat mendapatkan tuntutan pidana”.130 Pada tahun 1917, kejahatan yang hendak dituntut serupa dengan yang kemudian 128 “Charter of the International Military Tribunal”, 8 Agustus 1945, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 82 (1945): 279. 129 Lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 8-20. 130 Lihat umumnya Egon Schwelb, “Crimes against Humanity”, British Yearbook International 23 (1946): 178 (menggambarkan perkembangan konsep sejak Konvensi Den Haag, 1907). Untuk diskusi internasional tentang pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan, lihat Roger S. Clark, “Crimes against Humanity at Nuremberg”, dalam Johns Ginsbergs dan V.N. Kudriavstev (eds.), The Nuremberg Trial and International Law, (Norwell, Mass: Kluwer Acdemic Publishers, 1990, 177-78 (mengutip Commission on the Responsibility of the Authors of War and on Enforcement of Penalties) (laporan yang dipresentasikan pada Konferensi Pendahuluan tentang Perdamaian, dicetak ulang dalam Pamflet No. 32, Carnegie Endwment for International Peace). Lihat juga James Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Prosecuting War Criminals of the First Worl War, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982. 42 diberikan dalam instrumen pasca-Perang Dunia Kedua: pembunuhan, penyiksaan dan penindasan berdasar ras terhadap minoritas oleh pemerintahnya sendiri. Pada saat perencanaan Piagam London dan Control Council Law No. 10, Komisi Kejahatan Perang PBB mendefinisikan istilah Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai “tindakan massal secara sistematik”, dalam arti: Kejahatan yang baik karena tingkatnya atau karena kekejamannya atau karena jumlah besarnya atau karena pola serupa dilakukan di berbagai tempat dan waktu, dapat membahayakan komunitas internasional atau mengguncang kesadaran umat manusia, memerlukan intervensi dari negara-negara selain negara tempat terjadinya kejahatan tersebut, atau yang warganya menjadi korban. Secara historis, jurisprudensi ini menjelaskan penghilangan batasan kekuasaan negara atas dasar hak-hak individual. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ilustrasi paling jelas dan paling ideal tentang potensi hukum untuk mengadakan transisi normatif. Hukum menjadi paling signifikan apabila jurisdiksi terhadap suatu pelanggaran dikeluarkan dari wilayah tempat terjadinya dan dengan demikian menghilangkan pengaruh politik lainnya. Pemikiran ini tampak bila negaranegara melakukan respon terhadap kekejaman dalam cara-cara yang mengabaikan batas negara; jadi, bentuk respons ini sendiri merupakan pelaksanaan norma keadilan yang transenden. Setelah penggunaannya selama bertahun-tahun, ajudikasi untuk kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi identik dengan respon terhadap penindasan di masa modern. Ciri utama dari penindasan politik adalah bahwa ia melampaui kejahatan biasa dan menimbulkan respon internasional. Dalam bentuk modernnya, kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah semata-mata serangan negara terhadap warga negara asing, namun pelanggaran yang dilakukannya terhadap warganya sendiri, atau menganggap warga negaranya sendiri sebagai musuh, sehingga mendestabilisasi tatanan internasional bahkan pada masa damai. Prinsip jurisdiksional yang dapat diterapkan akan melampaui batasan tradisional teritori dan pembatasan waktu. Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh umat manusia, dan dengan demikian dapat diadili oleh semua negara, yang menimbulkan prinsip jurisdiksional lain yang terkait, yaitu: “universalitas”. Sementara pelanggaran pidana harus diketahui dan dituliskan dalam hukum, agar tidak melanggar prinsip mendasar yaitu retroaktivitas, kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai pelanggaran “menurut negara-negara beradab” dan dengan demikian bisa dihukum bahkan tanpa legislasi lebih dahulu. Pengecualian kejahatan terhadap kemanusiaan dari larangan legislasi retroaktif telah diratifikasi sebagai bagian dari Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi. Pasal 7 (2) mengecualikan pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan dari batasan retroaktivitas: “Pasal ini tidak menolak pengadilan dan penghukuman terhadap semua orang untuk semua tindakan, yang pada waktu dilakukannya, dianggap sebagai kejahatan menurut prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab”.131 Prinsip universalitas pada kejahatan terhadap kemanusiaan dicontohkan oleh pengadilan Adolf Eichmann atas kejahatan yang ia lakukan di Eropa pada Perang Dunia 131 “European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, 4 November 1950, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 312, No. 2889 (1955): pasal 7 (2). 43 Kedua. Meskipun pengadilan dilakukan puluhan tahun setelah terjadinya pelanggaran, di negara Israel, itu tidak dianggap melanggar prinsip retroaktivitas maupun teritorialitas.132 Kalau menurut prinsip teritorialitas tradisional, komunitas yang mengalami pelanggaran harus ada di wilayah terjadinya kejahatan, maka kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap seluruh komunitas umat manusia. Pemahaman serupa tentang universalitas mendasari proses kejahatan terhadap kemanusiaan kontemporer.133 Pada pengadilan kejahatan Perang Dunia Kedua yang dilakukan belakangan, seperti yang disidangkan di Kanada, jurisdiksi diberikan kepada kejahatan yang “bisa diadili di Kanada” pada saat terjadinya.134 Pengadilan di Spanyol untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Argentina dan Cili berdasarkan pada pemahaman universalitas yang serupa.135 Penerapan konsep jurisdiksi universal memiliki arti proyeksi ke belakang sekaligus prospektivitas yang konstruktif. Konstruksi ini merupakan bagian dari legalitas transisional, karena ia menyelesaikan dilema pergeseran normatif sambil menaati prinsip kedaulatan hukum konvensional yaitu stabilitas dan kontinuitas hukum. Dengan kaitan politik yang ada pada penindasan, ajudikasinya sering kali mengambil salah satu dari dua bentuk: atau pelanggaran tersebut diadili di negara lain, yang memiliki jurisdiksi dengan kondisi politik yang lebih liberal, seperti dibicarakan di atas, atau diadili di tempat kejahatan tersebut terjadi, namun setelah jangka waktu tertentu. Dalam salah satu dari kedua konteks itu, pengadilan terhadap pelanggaran, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi politik, tidaklah didorong oleh keduanya, dan menunjukkan persistensi respon hukum terhadap pelanggaran berat dan kekuatan normatifnya. Paradoks Jangka Waktu Pertimbangkanlah fenomena pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak mengenal batas waktu. Kasus-kasus tersebut mengaitkan lebih dari satu rezim, menarik benang merah politik melalui tempat dan waktu, dan memelihara perasaan tanggung jawab terhadap kesalahan di masa lalu yang pada akhirnya membangun identitas politik negara yang bertahan lama. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip jurisdiksional yang lazim, seperti batasan waktu. Terdapat selang waktu hampir setengah abad antara pemerintahan teror Nazi dan komunis dan pengadilan suksesor masing-masing, yang mungkin tidak sesuai dengan intuisi normal kita tentang cara kerja peradilan pidana.136 Lebih dari 132 Government of Israel v. Adolf Eichmann, Keputusan Mahkamah Agung (1962), bagian 11-12. Lihat Tadic, dicetak ulang dalam International Legal Materials 35 (1996): 32. 134 Lihat Criminal Code, R.S.C., bab c-46, § 6 (1.91) (Kanada, 1985), diperbaiki dalam bab 37, 1987 S.C. 1105. 135 Ini juga merupakan pemikiran House of Lords. Lihat UK House of Lords In re Pinochet, dicetak ulang dalam Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause (15 Januari 1999), tersedia di http://www.parliament.the-stationery.off...pa/Id199899/Idjudgmt/jd 990115/pin01.htm. Terdapat pula pengadilan lain dengan pendekatan jurisdiksional yang serupa. Lihat juga “Orden de Prisiόn provisional incondicional de Leopoldo Fortunato Galtieri, Juzgado Número Cinco de la Audiencia Nacional Española” (25 Maret 1997), tersedia di http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/autogalt.html. 136 Tentang masalah selang waktu dan respon legal, lihat David Matas, Justice Delayed: Nazi War Criminals in Canada, Toronto: Summerhill Press, 1987; Peter Irons, Justice at War: The Story of Japanese American Internment Cases, New York: Oxford University Press, 1983; Harold David Cesarani, Justice Delayed, London: Mandarin, 1992; Allan A. Ryan, Jr., Quiet Neighbors, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984. Lihat juga 133 44 setengah abad setelah terjadinya, pengadilan terhadap kasus Perang Dunia Kedua diadakan di seluruh Eropa, Kanada dan Australia. Usaha peradilan kriminal lazimnya dihentikan seiring perjalanan waktu, yang dicerminkan dengan adanya batasan waktu dalam hampir semua sistem hukum, bahkan untuk kejahatan-kejahatan berat. Hanya beberapa negara yang mengikuti sistem hukum Anglo-Amerika tidak memiliki batasan demikian bagi kejahatankejahatan yang berat. Perdebatan tentang apakah kejahatan terhadap kemanusiaan perlu dibatasi oleh waktu yang umumnya berlaku bagi kejahatan lainnya diletakkan dalam konteks proses pasca-perang, ketika pada tahun 1965, menurut hukum yang pada waktu itu berlaku, di mana batasan waktunya adalah dua puluh tahun. Di Jerman, meskipun terdapat usaha parlmenter untuk menghentikan pengadilan, statuta pembatasan ditunda dua kali, dengan alasan bahwa selama masa pendudukan, pengadilan Jerman tidak memiliki kedaulatan untuk mengadili. Akhirnya, pada tahun 1979, jawaban terhadap pertanyaan substantifnya tidak bisa lagi ditunda: sejauh mana kejahatan terhadap kemanusiaan dapat disetarakan dengan kejahatan biasa, dan dengan demikian bisa dibatasi jangka waktunya, ataukah kejahatan-kejahatan itu merupakan pelanggaran luar biasa yang berada di luar parameter jurisdiksi normal? Setelah perdebatan panjang, keputusannya adalah untuk membatasi praktis semua pengadilan yang terkait dengan perang, kecuali yang melibatkan “pembunuhan mendasar”, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan rasial atau sadis137 dengan motif untuk penindasan, seperti diimplikasikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tingkat internasional, dilema ini dituntaskan dengan pengesahan konvensi PBB tentang Ketidakberlakuan Batasan Statutoris terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.138 Standar jurisdiksional khusus yang berlaku pada kejahatan terhadap kemanusiaan akan dimasukkan ke dalam hukum nasional. Jadi, misalnya di Prancis, “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah satu-satunya pelanggaran yang dikecualikan dari statuta pembatasan waktu yang ketat di negara tersebut.139 Intuisi kita adalah bahwa keinginan politis untuk melakukan pengadilan akan berkurang setelah jangka waktu yang lama. Namun, dalam kasus pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang terjadi adalah kebalikannya. Signifikansinya tidak berkurang oleh waktu. Pertimbangkanlah mengapa ini terjadi. Sifat penindasan politik, terutama keterlibatan negara dalam pelanggaran ini, memiliki dampak terhadap efek perjalanan waktu. Penindasan secara sistemik bertentangan dengan asumsi pembuktian dan jurisdiksional berkaitan dengan perjalanan waktu. Bila negara terlibat dalam pelanggaran, berbagai aspek penting dari pelanggaran sering kali ditutup-tutupi dan tidak diketahui publik pada saat terjadinya, dan baru muncul setelah waktu yang lama: bukan hanya identitas para pelakunya, namun yang lebih penting, fakta-fakta dan karakter pelanggaran itu sendiri. Terlebih lagi, implikasi negara dalam Ronnie Edelman et al., “Prosecuting World War II Prosecutors: Efforts at an Eras’s End”, Boston College Third Law Journal 12 (1991): 199. 137 Lihat Federal Supreme Court in “Criminal Cases” Vol. 18, 37 (Jerman) (menafsirkan Pasal 211 Penal Code yang mendefinisikan pembunuhan). Pelanggaran domestik yang relevan dalam hukum Jerman adalah pembunuhan yang dilakukan dengan “motif mendasar”. Lihat Robert Monson, “The West German Statute of Limitations on Murder: A Political, Legal, and Historical Explanation”, American Journal of Comparative Law 30 (1992): 605. 138 “Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity”, U.N. General Assembly Resolution 2391 (XXIII), 11 November 1970. 139 Lihat Law No. 64-1326, 29 Desember 1964 (Dalloz, Code Penal 767, 1970-1971). Lihat juga Journal Official de la Republique Francaise, 29 Desember 1964, 11.788; Pierre Mertens, “L’Imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre I’humanité,” Revue de Droit Penal et de Criminologie 51 (1970): 2004. 45 pelanggaran, dan juga dalam usaha untuk menutupinya, meningkatkan kemungkinan politisasi terhadap kebijakan penghukuman. Dalam pengadilan pasca-Perang Dunia Kedua, dorongan politik untuk mengadili meningkat, berkurang dan meningkat lagi seiring perjalanan waktu. Tepat ketika perang berakhir, masih terdapat keinginan besar untuk mencapai keadilan dari pihak Sekutu, namun kemudian dengan adanya Perang Dingin dan pergeseran politik, dorongan ini menyusut. Perjalanan waktu memiliki arti pergantian rezim yang akan memungkinkan usaha pencarian keadilan. Misalnya, transisi menuju demokrasi pada dekade 1980-an di Bolivia memungkinkan ekstradisi ke Prancis dan pengadilan terhadap antek Nazi, Klaus Barbie, lebih dari empat dekade setelah kekejaman-kekejaman yang ia lakukan.140 Perubahan rezim sering kali mendorong pembuktian, seperti dengan memberikan akses pada arsip pemerintah dan sumber lain tentang rezim pendahulu, sehingga memungkinkan tercapainya keadilan. Misalnya, perubahan politik di bekas blok komunis berarti akses lebih banyak pada arsip KGB dan partai komunis, menghasilkan arus informasi yang memungkinkan pengadilan. Akhirnya, bukti baru muncul secara kebetulan setelah jangka waktu tertentu. Misalnya, beberapa peristiwa kebetulan mengarah pada pengadilan nasional di Jerman, ketika pada pertengahan dekade 1950-an di kota Ulm ditemukan secara kebetulan keterlibatan Nazi pada masa lalu dalam suatu kasus non-pidana.141 Penemuan ini mendorong penyelidikan yang akhirnya berpuncak pada program pengadilan Perang Dunia Kedua di Jerman. Dalam contoh lain yang lebih mutakhir, dua dekade setelah pemerintahan junta di Argentina, pengakuan seorang anggota angkatan laut tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang ia lakukan (penghilangan) membuka kembali peristiwa-peristiwa masa tersebut. Apa yang disebut sebagai “Efek Scilingo”142 ini mendorong penyelidikan baru terhadap penghilangan dan penangkapan kembali terhadap para pemimpin junta. Sifat persisten pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa perjalanan waktu dalam hal ini bekerja secara paradoksal dan bertentangan dengan intuisi normal kita. Bahkan setelah beberapa generasi, rezim penerus tetap mengadili kejahatan rezim lama, meskipun tidak dengan sanksi yang berat. Jurisprudensi persistensi pengadilan ini tidak dijelaskan dengan baik oleh argumen peradilan pidana tradisional. Dengan bertambahnya usia para korban dan pelaku, tujuan retributif menjadi kehilangan signifikansinya. Dengan persidangan puluhan tahun setelah terjadinya pelanggaran, proses tersebut nyaris tidak memajukan tujuan penghukuman tradisional (traditional penal) untuk penggentaran atau perbaikan. Terlebih lagi, bahkan tujuan keadilan yang memandang ke depan, seperti untuk membangun demokrasi, menyusut karena berbagai perubahan politik telah menjadi sasarannya. Namun, perdebatan tentang apakah proses penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan perlu dilanjutkan setelah jangka waktu yang lama menunjukkan pengakuan terhadap beratnya pelanggaran tersebut dalam spektrum pelanggaran. Pada perdebatan PBB tentang Konvensi Ketidakberlakuan Batasan Statutoris terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, pencabutan batasan waktu dijustifikasi pada dasar 140 Lihat Barbie, 78 ILR 125. Rückerl, Investigation of Nazi Crimes, 48. 142 Lihat Martin Abregu, La Tutela Judicial del Derecho de la Verdad en la Argentina, 24 Revista IIDH (1996), II, 12-15. 141 46 “kekejaman” yang luar biasa dari kejahatan tersebut.143 Dalam perdebatan Jerman tentang statuta pembatasan waktu, perpanjangan waktu dijustifikasi secara normatif, berdasarkan pada beratnya kejahatan. Pada perdebatan lebih lanjut tentang pengadilan, penghargaan bagi kehormatan para korban, dan juga implikasi pengampunan terhadap perlindungan hak-hak mereka secara setara di muka hukum, menjadi tujuan yang sering terdengar.144 Perasaan “sekarang atau tidak sama sekali” dan keinginan untuk memberikan perlindungan yang setara bagi hak-hak para korban terlihat dalam peran penting mereka dalam peradilan berkaitan dengan perang pada akhir masa tersebut. Ini terlihat dalam pengadilan pasca-perang yang tertunda terhadap Klaus Barbie, Paul Touvier dan Maurice Papon di Prancis. Hal serupa terjadi di Inggris, di mana para kelompok korban menunjukkan keberadaan para tersangka pelaku kejahatan perang Nazi kepada otoritas pemerintahan Inggris.145 Peran para korban dalam peradilan transisional bervariasi secara dramatik dalam berbagai budaya hukum. Dalam hukum kontinental, para korban melakukan penuntutan, di mana mereka berperan sebagai penuntut privat, seperti dalam prosedur partie civile di Prancis dan querellante di Amerika Latin. Dalam hukum Anglo-Amerika, partisipasi pihak privat dalam proses pidana dianggap bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan mengancam kedaulatan hukum.146 Respon hukum di sini bekerja dengan cara simbolis, mengekspresikan suatu pesan yang menunjukkan ketaatan negara pada kedaulatan hukum.147 Perkembangan hukum internasional selama bertahun-tahun memperluas definisi kejahatan terhadap kemanusiaan lebih lanjut lagi hingga penindasan modern. Pada gilirannya, hal ini memberikan batasan bagi kedaulatan negara, yang bahkan mencakup kedaulatan negara untuk memberikan atau tidak memberikan hukuman. Konseptualisasi penindasan diawali dengan pandangan “objektif” yaitu status para korban yang dilindungi. Sehingga secara historis, kejahatan tehadap kemanusiaan didefinisikan dengan status warga sipil dalam kondisi perang dan pelanggaran yang mencakup penindasan etnik, keagamaan dan rasial. Konseptualisasi kontemporer lebih luas, karena ia tidak hanya terbatas pada perlakuan terhadap warga negara asing, namun juga mencakup pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negara yang sama bahkan dalam kondisi damai, sehingga melindungi warga dari penindasan berdasarkan ras, etnik, agama atau politik. Jadi, dalam pengadilan pada tahun 1987 terhadap Klaus Barbie, kepala Nazi di Lyons masa pendudukan, karena memerintahkan deportasi ke kamp-kamp pembunuhan, isu kritisnya adalah apakah anggota kelompok resistance (pejuang gerilya) yang bersenjata, korban yang 143 United Nations, Ecosoc, Commission on Human Rights, sesi ke-22, Question of Punishment of War Criminals and of Persons Who Have Committed Crimes against Humanity: Question of the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, diserahkan oleh Sekretaris-Jenderal, 1966, hlm. 84. 144 Untuk tinjauan tentang argumen Jerman untuk mencabut statuta pembatasan waktu terhadap pembunuhan era Perang Dunia Kedua, lihat Martin Clausnitzer, “The Statute of Limitations for Murder in the Federal Republic of Germany”, International and Comparative Law Quarterly 29 (1980): 478; Monson, “The West German Statute of Limitations on Murder”, 618-25. Lihat juga Jaime Malamud-Goti, “Punishment and a Rights-Based Democracy”, Criminal Justice Ethics 3 (musim panas/gugur 1991). Tentang peran para korban dalam usaha penghukuman, lihat Jeffrie G. Murphy, “Getting Even: The Role of the Victim”, dalam Ellen Frankel Paul et al. (eds.), Crime, Culpability and Remedy, Cambridge, Mass: Blackwell, 1990, 209. 145 Lihat “Questions of Justice”, The All-Party Parliamentary War Crimes Group 1, debat parlementer, House of Lords Official Report 1079 (1990). 146 Lihat Young v. Vuitton, 481 US 787, 811-12 (1987). Lihat juga George Fletcher, With Justice for Some: Victims’ Rights in Criminal Trials, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1995. 147 Tentang otoritas moral korban, lihat Skhlar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials. 47 statusnya sebagai warga sipil yang dilindungi tidak jelas, akan dilindungi oleh cakupan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Pada akhirnya menurut mahkamah agung Prancis, pertanyaan relevannya adalah bukan status para korban, namun tujuan tindakan yang dilakukan para tertuduh. Yang menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tujuannya untuk menindas.148 Penindasan didefinisikan oleh pengadilan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis atas nama “negara yang mempraktikkan kebijakan supremasi ideologis”.149 Dalam contoh kontemporer lainnya, doktrin perlindungan dari tribunal kejahatan perang internasional ad hoc tidak hanya mencakup masa pasca-perang, namun melampaui batasan antara penduduk sipil dan kombatan, perang dan damai. Jurisprudensi transisional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berevolusi dari sekadar status atributif – ke motif penindasan.150 Pemahaman kontemporer tentang tindakan-tindakan tidak manusiawi pada akhirnya berfokus pada kebijakan negara, dan dengan demikian menjelaskan mengapa, meskipun terdapat selang waktu yang panjang, kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dianggap perlu mendapatkan hukuman. Meskipun keterlibatan negara tidak dijadikan sebagai syarat, penindasan merupakan kejahatan yang sedemikian berat, sehingga bahkan jika negara tidak terlibat secara terbuka, pelanggaran tersebut dilakukan dengan latar belakang kebijakan pemerintahan. Dalam elaborasinya yang paling mutakhir, dalam kodifikasi untuk pengadilan pidana internasional permanen, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan dengan “serangan yang luas atau sistematis terhadap kelompok penduduk sipil apa pun”.151 Kebijakan penindasan memiliki arti liabilitas atau pertanggungjawaban kolektif, dengan konsekuensi yang berlanjut terhadap identitas politik negara sepanjang waktu. Penindasan melampaui korban-korban secara individual dan pelaku, dengan implikasi bagi masyarakat secara keseluruhan. Bila negara terlibat dalam penindasan, hal-hal mendasar tentang peradilan pidana menjadi terancam; persekongkolan, usaha menutup-nutupi kebenaran, dan halangan lainnya mempengaruhi kemungkinan untuk mencapai keadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan dampak peran negara dalam kesalahan di masa lalu sebagai elemen penting kondisi peradilan yang terkompromi pada masa transisi. Bahkan, faktor ini bisa banyak menjelaskan mengapa timbul ketegangan apabila rezim penerus tidak merespon ketidakadilan, 148 Barbie, 78 ILR 139-40. Lihat juga Jugement de Maurice Papon (21 April 1998) (didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan). 149 Barbie, 78 ILR 128. 150 Lihat Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, 1173. Lihat juga Tadic, dicetak ulang dalamn International Legal Materials 35 (1996): 32, 48-73. 151 Pasal 7 dari Rome Statute of the International Criminal Court meluaskan definisi “kejahatan terhadap kemanusiaan” seperti berikut ini: [T]indakan berikut ini bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis, dilakukan terhadap kelompok masyarakat sipil manapun, dalam bentuk: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan paksa terhadap penduduk; (e) pemenjaraan ...; (f) penyiksaan; (g) pemerkosaan, perbudakan seksual ...; (h) penindasan terhadap kelompok atau kolektif yang diidentifikasi atas dasar ... politik, rasial, nasional, etnik, budaya, agama, jender ...; (i) penghilangan paksa manusia; (j) kejahatan apartheid; dan (k) tindakan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter serupa ... Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Pasal 7, U.N. doc. A/ Conf.183/9 (17 Juli 1998) 48 di mana hal itu sendiri merupakan salah satu petunjuk kondisi tidak ideal dari keadilan transisional. Dalam pergantian rezim, masalah tersebut mengarah pada konstruksi pemahaman tentang tanggung jawab pidana yang berlanjut yang dikenal sebagai “impunitas”. Anggapan tentang pelanggaran yang berkelanjutan ini (bila tidak ada hukuman) merekonseptualisasi pelanggaran tersebut. Lebih lanjut lagi, logika ini menjustifikasi pencabutan batasan waktu konvensional terhadap pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti juga pemikiran analog dalam hukum pidana biasa yang menjustifikasi pencabutan batasan waktu terhadap pelanggaran seperti penipuan atau konspirasi yang melibatkan pejabat negara, karena keterlibatan negara memiliki konsekuensi yang membatasi kemungkinan tercapainya keadilan. Masalah ini menjadi lebih parah dalam rezim penindas bila mereka yang seharusnya menjadi pelaksana keadilan malah menjadi pelanggarnya. Bila negara terlibat dalam penindasan, kesetaraan dan keamanan di bawah hukum menjadi terancam. Dengan demikian, signifikansi respon transisi melampaui kasus individual untuk mengekspresikan pesan normatif tentang perlindungan yang setara, yang merupakan dasar kedaulatan hukum. Pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan membantu mengkonstruksikan pergeseran normatif transisional dengan mengutuk represi di masa lalu sambil sekaligus memperkuat pengembalian keamanan dan kesetaraan menurut hukum. Implikasi normatif respon legal ini melampaui masa transisi. Pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan signifikansi berlanjut respon negara terhadap penindasan. Pada akhir abad ke-20, penindasan sebagai kebijakan sistematis tidak diragukan lagi dianggap sebagai paradigma tirani modern. Dalam jurisprudensi kejahatan terhadap kemanusiaan, sanksi terkuat hukum merupakan respon kritis terhadap kebijakan represif di masa lalu. Bila penindasan di masa lalu “disahkan” oleh hukum, pengadilan terhadapnya menunjukkan perbedaan normatif dan pergeseran ke legalitas yang baru. Peradilan pidana digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara pemerintahan liberal dan non-liberal. Penerapan hukuman untuk kejahatan terhadap kemanusiaan memberikan perlindungan bagi hak-hak yang terkait pada perbedaan kontemporer antara pemerintahan otoriter dan liberal. Peradilan pidana suksesor bisa membantu menjelaskan signifikansi pengadilan kontemporer lainnya. Jadi, sebagai contoh, dalam jurisprudensi konstitusional Amerika, diskriminasi yang disponsori negara mendapatkan perhatian konstitusional yang paling ketat. Pentingnya pengadilan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah ras ini, bahkan setelah selang waktu yang panjang, bisa dipahami dalam konteks sejarah Amerika yang mengalami diskriminasi rasial yang disponsori negara, yang menimbulkan masalah keadilan transisional yang belum terselesaikan. Bahkan bila pelanggaran rasis disponsori secara pribadi, hal itu mengingatkan orang pada penindasan yang didukung negara di masa lalu, dan menimbulkan kemungkinan tanggung jawab kolektif yang berlanjut, dengan potensi konsekuensi sosial yang parah kecuali bila ada respon yang transformatif.152 Peradilan Pidana Transisional: Beberapa Kesimpulan Peradilan pidana transisional tidak hanya memajukan tujuan-tujuan hukuman yang konvensional dalam negara yang taat kedaulatan hukum. Peran peradilan pidana dalam saat 152 Ilustrasi mutakhir tentang hal ini adalah pengadilan ketiga terhadap pembunuhan Medgar Evers. Mississippi v. Byron De La Beckwith, 702 S2d 547 (Miss., 1997), cert. denied, 525 vs 880 (1998). 49 transisi, seperti ditunjukkan pengalaman di atas, melampaui penghukuman konvensional. Ia melampaui unsur-unsur yang lazim terdapat dalam peradilan pidana, seperti penggentaran, yang telah terdapat dalam reformasi politik dan dimajukan oleh proses itu, yang menyertai transisi, di mana perubahan dalam struktur institusional negara mempengaruhi pertimbangan konsekuensi dari tindakan yang mungkin akan dilakukan. Namun, peradilan transisional memajukan tujuan lainnya yang khas pada perubahan politik, seperti memajukan tercapainya kedaulatan hukum dalam masa transisi. Tujuan-tujuan inilah yang menimbulkan dilema tentang peran hukum dalam masa perubahan politik: utamanya, bagaimana mendamaikan perubahan normatif dengan ketaatan pada legalitas konvensional. Dilema ini dituntaskan dalam praktik transisional di atas dengan membatasi hukuman dalam proses parsial dan simbolik, suatu dasar perubahan yang dikendalikan dengan baik. Sanksi transisional ini memiliki peran kompleks dalam transformasi politik: hukum ikut membangun transisi, mengutuk tindakan salah di masa lalu – bahkan sambil ia meninggalkannya di masa lalu – sementara memperkuat ketaatan pada kedaulatan hukum. Transisi bervariasi dalam hal sejauh mana beragam transisi itu mendorong transformasi norma yang lebih substansial. Jika rezim lama dipertahankan oleh kebijakan penindasan yang dirasionalkan oleh sistem “hukum”, pertimbangan inilah yang ditentang oleh respon hukum kritis. Melampaui peran hukum pidana konvensional dalam menunjukkan keberlakuan dan melindungi nilai-nilai yang telah ada,153 hal yang membedakan respon pidana transisional adalah usahanya untuk mengadakan dan memperkuat perubahan normatif. Usaha ini terlihat jelas dalam fokus khusus respon transisional dari berbagai negara untuk “membongkar” kekerasan politik masa lalu melalui proses penyelidikan dan penuntutan, dua ritual pengetahuan kolektif yang memungkinkan pengutukan terhadap pelanggaran di masa lalu.154 Respon kritis terhadap penindasan di masa lalu ini menjelaskan bahwa kebijakan adalah buatan manusia, dan dengan demikian dapat diperbaiki. Dengan pengetahuan tentang kesalahan di masa lalu dan pembebanan tanggung jawab kepada individu pelaku, kemungkinan untuk perubahan menuju demokrasi bisa tercapai. Dengan cara ini, sanksi pidana transisional membebaskan rezim penerus dari kesalahan-kesalahan pendahulunya di masa lalu. Melalui proses hukum yang teritualisasi soal pencaplokan atau pelepasan, penerimaan dan penolakan, kehilangan dan penerimaan, masyarakat bergerak ke arah yang lebih liberal, melalui proses yang memungkinkan transformasi dan kemungkinan penebusan kesalahan.155 Suatu bentuk peradilan pidana, seperti ditunjukkan praktik transisional, merupakan ritual dari negara-negara yang sedang menuju demokrasi, karena melalui praktik ini normanorma dikemukakan ke masyarakat. Melalui proses yang dikenal dan ketat, ditariklah suatu garis, membebaskan masa lalu, yang memungkinkan masyarakat untuk bergerak maju. Meskipun hukuman secara konvensional dianggap cenderung retributif, dalam masa transisi, tujuannya adalah korektif, tidak hanya kepada pelaku individual tetapi ke masyarakat secara luas. Tujuan ini dilihat dalam sikap terhadap pelanggaran politik sistematis, misalnya dalam persistensi untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan – pelanggaran politik yang menindas, yang merupakan respon kritis terhadap pemerintahan non-liberal melalui hukum 153 Lihat Joel Feinberg, Doing and Deserving, Princenton: Princenton University Press, 1970. Lihat Girard, Violence and the Sacred. 155 Lihat umumnya Hart, Punishment and Responsibility, 170-73. 154 50 pidana. Terlebih lagi, sementara penghukuman konvensional dianggap memecah-belah masyarakat, dalam transisi, ketika penghukuman dilakukan, ia dilakukan secara terbatas untuk memungkinkan tercapainya sistem politik yang liberal. Dengan demikian, proses pidana memiliki kedekatan dengan respon nonkriminal lainnya, yang dibicarakan dalam bab-bab lain, yang menyusun keadilan transisional. Dalam keadilan transisional, dilema kedaulatan hukum menjadi penting karena kondisi yang luar biasa dari perubahan politik yang radikal. Namun masa-masa itu tidak terputus dari masa sebelumnya, namun secara jelas menggambarkan masalah-masalah yang biasanya kurang transparan dalam sistem peradilan yang lebih mapan, dan dengan demikian, jurisprudensi transisional bisa menjelaskan pemahaman kita tentang kebijakan peradilan pidana secara lebih umum. Yang paling signifikan, pengalaman di muka menunjukkan potensi hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen stabilitas, tetapi juga untuk perubahan sosial. 51 Bab 3 Keadilan Historis Bab ini mengeksplorasi respon historis terhadap peninggalan kekejaman di masa lalu dan pertanyaan tentang peran apa yang dimainkan oleh pertanggungjawaban historis dalam transisi menuju demokrasi. Transisi – dari sefinisinya – menunjukkan adanya diskontinuitas sejarah. Perang, revolusi dan pemerintahan represif merupakan masa-masa gelap dalam sejarah suatu bangsa yang mengancam kontinuitasnya. Pertanyaan yang timbul adalah: secara deskriptif, bagaimana masyarakat memperlakukan masa-masa cacat sejarah tersebut? Sejauh mana peran respon historis terhadap pemerintahan otoriter di masa lalu? Dan secara normatif, dalam hal apa pertanggungjawaban historis merupakan hal yang korektif dan mendorong liberalisasi? Suatu pandangan yang populer di kalangan analis politik kontemporer adalah bahwa penyidikan dan dokumentasi sejarah yang mengasimilasikan masa lalu yang buruk merupakan hal yang diperlukan untuk mengembalikan kolektivitas pada masa-masa perubahan politik yang radikal. Klaim mereka adalah bahwa dengan menemukan “kebenaran” tentang kesalahan-kesalahan negara di masa lalu, seperti melalui konstitusi baru atau pengadilan suksesor, hal tersebut membantu untuk meletakkan dasar bagi tatanan politik yang baru. [P]emerintahan penerus memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menentukan fakta-fakta, sehingga kebenaran diketahui dan dijadikan bagian dari sejarah suatu bangsa ... Perlu ada pengetahuan dan pengakuan: peristiwa-peristiwa di masa lalu harus diakui keberadaannya secara resmi dan diungkapkan secara terbuka. Pengungkapan kebenaran .... merespon tuntutan untuk mendapatkan keadilan dari para korban dan memfasilitasi rekonsiliasi nasional.1 Seperti klaim normatif konstitusi dan pengadilan di masa transisi, klaim normatif untuk menyusun dokumentasi sejarah yang resmi adalah bahwa ia memungkinkan pergeseran menuju tatanan yang lebih liberal. Penyusunan sejarah kolektif tentang masa lalu yang represif dianggap meletakkan dasar yang diperlukan untuk masyarakat demokratis yang baru. Dikatakan bahwa proses ini mutlak diperlukan untuk transisi menuju demokrasi: sejarah transisional yang diarahkan pada masa depan yang lebih baik menggambarkan suatu proses dialektis dan progresif. Pandangan ini mewarisi semangat dari masa lalu, dari masa pencerahan – Immanuel Kant hingga Karl Marx, yang menganggap bahwa sejarah bersifat menguniversalkan dan memberikan penebusan. Dalam pandangan ini, sejarah adalah pengajar dan hakim, dan kebenaran sejarah itu sendiri merupakan keadilan. Pandangan tentang potensi liberalisasi dari sejarah inilah yang mendorong argumen kontemporer untuk pertanggungjawaban sejarah dalam transisi. Namun, asumsi bahwa “kebenaran” dan “sejarah” Alice H. Henkin, “Conference Report”, dalam State Crimes: Punishment or Pardon, dalam Alice H. Henkin (ed.), Queenstown, Md: Aspen Institute, 1989, 4-5. Terdapat banyak penganjur pandangan ini dalam komunitas diplomatik dan hak asasi manusia. Lihat misalnya Margaret Popkin dan Naomi Roht-Arriaza, “Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America”, Law and Social Inquiry 20 (Musim Dingin 1995): 79. Lihat juga José Zalaquett, “Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Rights Violations”, Hastings Law Journal 43 (1992): 1425; Timothy Garton Ash, The File: A Personal History, New York : Random House, 1997. 1 1 adalah hal yang satu dan yang sama2 menunjukkan suatu kepercayaan tentang adanya suatu sejarah yang otonom dan objektif tentang masa lalu, di mana konteks politik masa kini tidak memiliki peran dalam pembentukkannya. Namun, teori modern tentang pengetahuan sejarah menentang konsepsi ini.3 Bila sejarah disusun secara interpretatif,4 tidak ada pemahaman atau “pelajaran” yang tunggal, jelas dan mutlak tentang masa lalu, namun yang ada adalah pengakuan terhadap sejauh mana pemahaman tentang sejarah bergantung pada kondisi politik dan sosial. Bagian-bagian dari sejarah dalam masa demikian, seperti akan ditunjukkan di bawah, tergantung tidak hanya pada peninggalan sejarah dan politik di suatu wilayah, namun juga pada konteks khas transisi tersebut. Pandangan ideal tentang sejarah transisional sebagai “dasar”, atau sebagai titik awal, mengabaikan tinjauan sejarah yang sudah ada. Tinjauan sejarah yang disusun pada masa transisi tidaklah berdiri sendiri, namun didukung oleh narasi nasional yang telah ada. Latar belakang berupa ingatan kolektif yang sudah ada menentukan suatu masyarakat. Kebenaran transisional dikonstruksikan secara sosial dalam proses ingatan kolektif. Seperti tercermin pada praktik-praktik masyarakat dalam masa tersebut, tinjauan sejarah tidaklah terlalu bersifat mendasar sebagaimana ia bersifat transisional. Masa transisi adalah bagian dari sejarah yang diciptakan secara sadar. Masa tersebut adalah masa penciptaan sejarah dalam suatu konteks yang cenderung terpolitisasi dan didorong oleh kepentingan politik. Politik memiliki implikasi epistemiknya. Kaitan erat antara penyalahgunaan kekuasaan dan pengendalian pengetahuan dijelaskan secara mendalam oleh Friedrich Nietzsche dan Michel Foucault.5 Namun, bahkan intuisi modern menolak penyelidikan sejarah yang secara eksplisit dipolitisasi, karena hal tersebut bertentangan dengan pandangan ideal suatu filsafat sejarah yang dianggap merdeka dari pengaruh politik. Jadi, penyelidikan sejarah dalam masa transisi merupakan tantangan yang sukar. Sifat sejarah yang dipolitisasi, terkait dengan pemerintahan represif, diungkapkan oleh respon-respon dalam transisi. Meskipun tinjauan-tinjauan sejarah masing-masing dikaitkan dengan rezim politik yang berbeda, penggunaan pengetahuan dalam politik biasanya dikaburkan oleh para pemegang kekuasaan. Narasi sejarah selalu ada; semua rezim dikaitkan dan dikonstruksikan oleh suatu rezim “kebenaran”.6 Perubahan rezim politik dengan demikian berarti perubahan serupa dalam rezim kebenaran. Ingatan kolektif adalah proses merekonstruksi masa lalu dengan cara pandang masa kini.7 Namun, proses rekonstruksi ini memiliki bentuknya yang khas pada masa transisi. Pada Lihat R.G. Collingwood, The Idea of History, New York: Oxford University Press, 1994. Lihat Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Hostorical Profession, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Tentang narasi sejarah, lihat Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987, 13. 4 Lihat H.G. Gadamer, Truth and Method, New York: Crossroad, 1989. 5 Untuk diskusi lebih mendalam tentang peran ingatan dalam pembentukan masyarakat, lihat Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, terjemahan Walter Kaufmann dan R.J. Hollingdale, New York: Vintage Books, 1967; Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, terjemahan Colin Gordon et al., New York: Pantheon Books, 1980. 6 Lihat Foucault, Power/Knowledge. 7 Untuk karya mendasar tentang konstruksi ingatan kolektif, lihat Maurice Halbwachs, On Collective Memory, terjemahan Lewis A. Coser, Chicago: University Press, 1992. Dari perspektif sosiologi, lihat Iwona IrwinZarecka, Frames of Remembrance: The Dynamics of Collective Memory, New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 1994; Natalie Zeman Davis dan Randolph Stern (eds.), “Memory and Countermemory”, Representation 26 (1985); Jonathan Boyarin (ed.), Remapping Memory: The Politics of Timespace, Minneapolis: 2 3 2 masa-masa transformatif, kaitan antara konstruksi sejarah kolektif dan politik dicoba untuk diputuskan sekaligus dikaitkan dengan erat. Konstruksi sejarah pada masa-masa transformasi politik diciptakan dengan menarik garis diskontinuitas, namun pada saat yang sama, tetap ada kontinuitas sejarah dan politik hingga titik tertentu. Sejarah transisional memiliki narasinya sendiri, namun mengaitkan dan mengambil benang-benang sejarah yang telah ada. Perimbangan antara diskontinuitas dan kontinuitas, sebagaimana akan terlihat, adalah hal yang mendefinisikan praktik penciptaan sejarah transisional, membuatnya perlu dilakukan dengan hati-hati, sementara sekaligus memberinya potensi transformatif yang sesungguhnya. Suatu pemahaman tentang bagaimana politik yang sedang mendemokratiskan dirinya mempengaruhi konstruksi sejarah pada masa transformasi politik yang substansial pada akhirnya dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang peran sejarah dalam masa biasa. Pertanyaan tentang tinjauan sejarah pada masa perubahan politik yang mendasar adalah bagian dari pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat menciptakan kebenaran yang disepakati bersama. Konsensus epistemik dalam masyarakat dianggap diciptakan oleh mekanisme transmisi kebudayaan; arti kebenaran dalam masyarakat mensyaratkan pemahaman bersama hingga titik tertentu.8 Namun, dalam transisi, pemahaman bersama ini sering kali rapuh atau malah tidak ada. Apa yang terjadi bila suatu pemerintahan runtuh seperti terjadi pada masa represi? Siapakah pemegang otoritas pada masa transisi? Masalah yang muncul dalam masa perubahan politik radikal timbul dari ketiadaan kesamaan pandangan. Dalam masa ini, tidak ada pandangan tentang politik dan sejarah yang dimiliki bersama. Dalam transisi, kesamaan pandangan yang membentuk dasar bagi konsensus sosial yang baru diharapkan bisa timbul dari tinjauan terhadap sejarah. Bagaimana cara masyarakat mengkonstruksikan masa lalu mereka sedemikian rupa sehingga dipahami secara bersama sebagai kebenaran tentang pengalaman bersama? Bagaimana mereka menentukan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sejarah yang penuh perdebatan tentang kejahatan negara? Di bawah ini, proses-proses yang dilaksanakan dalam konstruksi sejarah transisi akan dibahas. Karena teori kontemporer menekankan kaitan prinsip interpretif pada konteks sosial dan politiknya, sejarah transisional menunjukkan kaitan tinjauan sejarah yang tertulis dengan bentuk dan format legal yang terjadi. Pertanggungjawaban yang didapatkan dari sejarah transisional diciptakan oleh bentuk-bentuk dan praktik-praktik dalam suatu sistem hukum. Sejarah transisional mengungkapkan bagaimana bentuk dan praktik hukum tertentu memungkinkan produksi sejarah dan mentransformasi kebenaran. Sejarah transisional juga menjelaskan kepada kita tentang peran sejarah dalam perubahan politik menuju sistem yang liberal. Pengalaman beberapa negara yang dibahas dalam bab ini menjelaskan berbagai bentuk pertanggungjawaban sejarah. Di sini dijelaskan bagaimana masyarakat mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengkonstruksikan suatu kisah milik bersama dalam perubahan politik yang radikal. Juga dijelaskan tentang berbagai cara masyarakat transisional menyusun sejarah bersama, dan peran hukum dalam konstruksi tersebut. Ingatan kolektif diciptakan dalam kerangka kerja, melalui simbol dan ritual. Dalam transisi, kerangka kerja University of Minnesota Press, 1994; Susan A. Crane, “Writing the Individual Back into Collective Memory”, American Historical Review 20 (1997): 1372. Untuk perspektif antropologi historis, lihat Gerald Silder dan Gavin Smith (eds.), Between History and Histories: The Making of Silences and Commemorations, Toronto: University of Toronto Press, 1997. 8 Untuk penjelasan tentang pandangan ini, lihat Steven Shapin, A Social History of Truth, Chicago: University of Chicago Press, 1994. 3 yang lazim – politik, agama, sosial – mendapatkan ancaman; sehingga hukum beserta kerangka dan prosesnyalah yang menyusun sebagian terbesar dari ingatan kolektif. Pada masa transisi, hukum berperan penting dalam membentuk ingatan sosial. Narasi sejarah transisional diciptakan melalui berbagai tindakan legal, seperti pengadilan terhadap rezim lama, atau badan-badan birokratik yang bersidang untuk mengungkapkan sejarah, dan berbagai respon legal lainnya yang mencoba menemukan kebenaran. Terakhir, kisah-kisah independen lainnya didapatkan dari inisiatif para jurnalis atau sejarawan, meskipun kisah-kisah ini pun bersumber dari hukum sebagai otoritas dan batasannya. Kisah sejarah dalam masa transisi politik mengambil berbagai bentuk. Sumber dan bentuk kebenaran transisional beragam: pengadilan, komisi kebenaran, sejarah resmi. Analisis di sini menunjukkan suatu fakta yang selalu ada namun terutama menonjol pada masa transisi: “Masing-masing masyarakat memiliki rezim kebenarannya, ‘politik umum’ kebenarannya; yaitu diskursus yang diterima secara umum dan berfungsi sebagai kebenaran”.9 Berbagai rezim kebenaran, yaitu susunan kebenaran, amat terlihat jelas dalam konteks transisional. Substansi rezim kebenaran transisional bergantung pada sifat rezim kebenaran yang telah ada, dan sejauh mana terjadi transformasi yang kritis. Sumber-sumber justifikasi sejarah transisional menentukan arah transformasi politik. Melalui kerangka hukum, bahasa, prosedur dan peristilahan dalam keadilan, rekonstruksi ini bisa berjalan maju. Di bawah ini dijelaskan beberapa contoh konstruksi ingatan kolektif dalam transisi. Sejarah Hukum: Keadilan Historis dan Pengadilan Pidana Sejak dulu, proses pengadilan memiliki peran terpenting dalam penyusunan sejarah transisional. Sejarah bertindak sebagai “hakim” dalam proses peradilan pidana. Dalam perdebatan kontemporer tentang keadilan transisional, masalah tersebut sering kali ditempatkan dalam kerangka “penghukuman atau amnesti”. Penghukuman dikaitkan dengan ingatan kolektif, dan ketiadaan hukuman dikaitkan dengan amnesti kolektif.10 Pertimbangkanlah peran penghukuman dalam usaha untuk mencapai keadilan historis. Pengadilan adalah suatu bentuk upacara yang lazim terjadi dalam penyusunan sejarah kolektif. Namun selain itu, pengadilan juga merupakan cara terpenting untuk memproses peristiwaperistiwa yang kontroversial.11 Tujuan peradilan pidana umumnya adalah untuk menentukan tanggung jawab individual dan untuk menentukan kebenaran tentang suatu peristiwa yang menimbulkan kontroversi. Meskipun nilai penting proses pengadilan pidana untuk menemukan kebenaran ini bervariasi antara sistem dan budaya hukum yang berbeda,12 pada masa transisi, peran pengadilan untuk menyelesaikan kontroversi sejarah tidak bisa dibantah. Foucault, Power/Knowledge, 131. Untuk kritik terhadap penggunaan pengadilan pidana untuk tujuan ingatan kolektif, lihat Mark J. Osiel, “Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre”, University of Pennsylvania Law Review 144 (1995): 463. 11 Tentang peran pengadilan sebagai ritus dalam ingatan sosial, lihat Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 12 Bandingkan Mirjan Damaska, “Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study”, University of Pennsylvania Law Review 121 (1973): 506, 578-86 (menganggap bahwa sistem kontinental lebih mementingkan penemuan kebenaran), dengan John H. Langbein, “The German Advantage in Civil Procedure”, University of Chicago Law Review 52 (1985): 823. 9 10 4 Karena transisi merupakan masa konflik politik dan sejarah yang terkait, pengadilan suksesor sering kali diadakan sebagai cara utama untuk mendapatkan keadilan historis. Pengadilan suksesor juga sering kali dilakukan untuk menyusun tinjauan sejarah dalam masa transisi politik; bahkan sering kali inilah tujuan utamanya. Melalui pengadilan, usaha untuk menemukan kebenaran sejarah ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban dan usaha untuk menemukan keadilan. Dalam beberapa aspeknya, penggunaan pengadilan untuk melakukan penyelidikan sejarah tentang hal-hal kontroversial sesuai dengan intuisi kita tentang fungsi epistemik penghukuman. Namun, sejarah transisional melalui pengadilan pidana melampaui pemahaman kita tentang peran pengadilan secara umum dalam pertanggungjawaban pidana, namun ia tetap dibentuk oleh cara pandang pengadilan tersebut. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban terhadap masa lalu mempengaruhi dan menyusun suatu pandangan tentang keadilan historis. Sejarah transisional pasti akan menyusun suatu tinjauan yang spesifik tentang masa lalu suatu negara yang kontroversial. Dalam tinjauan sejarah di proses peradilan pidana, kebenaran ditemukan bersama dengan keadilan, dan dengan demikian berperan dalam proses delegitimasi rezim pendahulu, dan melegitimasi rezim penerus. Meskipun keruntuhan militer atau politik bisa menjatuhkan pemimpin yang menindas, bila rezim tersebut tidak didiskreditkan secara terbuka, ideologi politiknya bisa bertahan. Jadi, perdebatan di abad ke-18 tentang apakah raja Louis XVI perlu diadili dilihat oleh Thomas Paine sebagai kesempatan untuk mengungkapkan “kebenaran” tentang kejahatan pemerintahan monarki: “Bila ia, sang raja, dilihat ... sebagai seorang tertuduh yang pengadilannya bisa mendorong negara-negara lain di dunia untuk mengetahui dan membenci sistem monarki yang mengerikan, serta rencana busuk dan intrik dalam pemerintahan mereka sendiri, maka ia perlu diadili”.13 Pengadilan suksesor penting lainnya, baik terhadap penjahat perang di Nuremberg atau junta militer Argentina, kini terutama diingat bukan karena hukuman yang mereka jatuhkan terhadap individu-individu, namun tentang peran mereka dalam menyusun catatan yang abadi tentang tirani negara. Proses pidana suksesor memungkinkan berbagai representasi sejarah dari peninggalan masa lalu yang kejam. Pengadilan memungkinkan representasi sejarah kolektif dengan jelas, melalui penciptaan kembalinya dan dramatisasi tentang masa lalu, dalam proses pidana. Terlebih lagi, tinjauan sejarah ini biasanya dicatat dalam transkrip tertulis, yang sering kali diterbitkan. Pada masa kontemporer, kemungkinan representasional ini sangat meningkat dengan media massa dan penyiaran proses pengadilan melalui televisi, yang menjadikannya bagian dari budaya populer. Catatan tertulis dan lainnya dari pengadilan dan keputusan merupakan representasi yang abadi. Bagaimana proses pidana mengkonstruksikan kebenaran?14 Tidak ada jawaban tunggal, karena berbagai aspek penemuan kebenaran dihasilkan dari berbagai bagian dalam proses pidana. Sebagai contoh, pengadilan pidana memungkinkan penyusunan catatan sejarah dengan standar kepercayaan hukum yang tinggi: dalam jurisprudensi Anglo-Amerika, Michael Walzer (ed.), dan Marian Rothstein (penrj), Regicide and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI, New York: Cambridge University Press, 1974, 129. 14 Untuk penelitian tentang kaitan prosedur pidana dengan kebenaran, lihat catatan kaki 12 di atas. Untuk pembicaraan tentang teori prosedur pidana “ekspresif”, lihat Ruti Teitel, “Persecution and Inqusition: A Case Study”, dalam Irwin P. Stotzky (ed.), Transition to Democracy in Latin America: The Role of the Judiciary, Boulder: Westview Press, 1993. 13 5 “kebenaran yang tidak diragukan”.15 Contoh utamanya adalah pengadilan dan keputusan di Nuremberg. Bukti-bukti kekejaman dalam pengadilan tersebut, yang sebagian besar berasal dari arsip Jerman sendiri, mencakup 10 ribu dokumen tentang pembuatan kebijakan. Terdapat preferensi untuk merujuk pada dokumen sebagai barang bukti, karena pengakuan dianggap memiliki kecenderungan politisasi. Menurut Penuntut Umum Robert Jackson, “kita tidak akan meminta Anda untuk mendakwa orang-orang ini atas kesaksian musuh-musuh mereka”. The Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals merupakan suatu catatan permanen tentang kebijakan penindasan Nazi, yang masih digunakan oleh para sejarawan dan pakar lainnya.16 Contoh lain yang lebih modern adalah pengadilan junta militer Argentina pada tahun 1983, yang memungkinkan pengungkapan masa lalu negara tersebut secara terbuka. Pengadilan terhadap junta militer ini, karena sistem hukum Argentina mengikuti sistem Eropa, merupakan pengadilan pertama yang dilakukan secara terbuka. Selama pengadilan junta ini, untuk pertama kalinya setelah kejatuhan pemerintahan militer, tindakan-tindakan penindasan oleh militer diungkapkan ke masyarakat melalui media secara terbuka selama jangka waktu yang cukup lama. Kebenaran tentang apa yang terjadi ditentukan dari kesaksian para korban dan dilengkapi oleh organisasi non-pemerintah internasional, kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing – semuanya menunjukkan kekejaman rezim lama.17 Sebuah pengadilan suksesor lainnya, terhadap mantan “kaisar” Afrika Tengah, JeanBedel Bokassa, juga penting dalam hal representasinya tentang kediktatoran yang telah berlalu. Setelah satu dekade pemerintahan represif, Bokassa digulingkan oleh Prancis dan diadili untuk tindakan-tindakan kekejaman, termasuk pembantaian politik dan bahkan kanibalisme. Melalui siaran televisi dan radio di seluruh negara tersebut, pengadilan panjang terhadap Bokassa menciptakan narasi lisan yang jelas tentang kekejaman kediktatorannya.18 Pada akhirnya, meskipun diberikan amnesti, pelaporan luas tentang proses pengadilan tersebut menjamin bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rezim Bokassa tidak akan dilupakan. Kekuatan pengadilan dalam membentuk ingatan kolektif dilihat dari perannya untuk membuat konstruksi sosial pengetahuan tentang suatu masa untuk jangka yang panjang. Kekuatan peradilan pidana dalam konstruksi sejarah mungkin paling jelas tergambar dalam kaitan antara proses pidana yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua dan kisah-kisah tentang masa tersebut. Penulisan sejarah (historiografi) pasca-perang merujuk pada pentingnya pengadilan dalam memandang dan menciptakan pemahaman sejarah. Kekuatan representasi legal dalam konstruksi pemahaman sejarah ilmiah dan populer tentang kekejaman masa perang tampak dalam arah pemahaman sejarah hingga kini. Pemahaman sejarah dan legal tentang penindasan berkembang secara sejajar, menunjukkan fungsi kuat hukum dalam konstruksi sejarah di masa transisi. Pemahaman sejarah awal tentang penindasan Nazi bersesuaian dengan pemahaman hukum tentang pertanggungjawaban yang dikonstruksikan pada pengadilan pasca-perang. Pemahaman tentang pertanggungjawaban terhadap penindasan di masa perang dimulai dengan memusatkan perhatian terhadap individu pada jajaran In re Winship, 397 US 358, 364 (1970); lihat John Calvin Jeffries, Jr. dan Paul B. Stephan III, “Defenses, Presumptions and Burden of Proof in Criminal Law”, Yale Law Journal 88 (1979): 1325, 1327. 16 Lihat Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986, 18. 17 Lihat Human Rights Watch, An Americas Watch Report: Truth and Partial Justice in Argentina, an Update, New York: Human Rights Watch, 1991. 18 Lihat Alex Shoumatoff, African Madness, New York: Random House, 1988, 93-127. 15 6 kekuasaan tertinggi. (Pemahaman ini kemudian akan bergeser, yaitu bahwa pertanggungjawaban lebih tersebar pada seluruh jajaran). Dengan demikian, di Nuremberg, kejahatan yang terberat adalah “penyelenggaraan perang yang agresif”, dan yang diadili adalah para petinggi militer. Bersamaan dengan sidang-sidang pengadilan awal terhadap para eselon tertinggi militer Jerman, mazhab sejarah pada masa itu pun memandang tanggung jawab sebagai suatu hal yang top down (dari atasan ke bawahan). Mazhab “intensionalis” ini menganggap kebijakan Nazi didominasi oleh Hitler; maka tanggung jawab untuk kekejaman di masa perang harus dibebankan pada para petinggi. Seiring jalannya waktu, timbullah pemahaman hukum yang lebih jelas tentang tanggung jawab, yang berjalan bersama dengan perubahan dalam pemahaman sejarah. Setelah Nuremberg, pengadilan-pengadilan Control Council No. 10 menunjukkan konstruksi pertanggungjawaban yang memindahkan beban tanggung jawab kejahatan perang dari jajaran tertinggi militer Jerman ke para elite sipilnya. Interpretasi sejarah dari masa ini bergeser dari mazhab intensionalis, yang menganggap tanggung jawab terkonsentrasi (pada satu orang), ke mazhab fungsionalis, yang menganggap tanggung jawab tersebar luas di seluruh sektor masyarakat Jerman, seperti di negara-negara lainnya.19 Pengadilan tingkat bawah menunjukkan pergeseran pemahaman yang serupa. Persidangan Eichmann berlangsung bersama dengan penulisan The Destruction of the European Jews oleh Raul Hilberg pada tahun 1961. Pada dekade-dekade selanjutnya, pengadilan diterapkan pada para kolaborator, juga bagian jajaran kekuasaan yang lebih rendah. Kolaborator masa perang diadili di negaranegara yang sempat diduduki Jerman, terutama Belanda dan Prancis. Contoh penting pengadilan tersebut adalah pengadilan Klaus Barbie pada 1987 dan Paul Touvier serta Maurice Papon pada 1990-an di Prancis. Proses hukum dilaksanakan di Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia dan Australia, kepada para pelaku penindasan yang melarikan diri ke negara-negara tersebut setelah akhir perang.20 Pengadilan dianggap tidak tepat untuk representasi sejarah yang memadai karena peradilan pidana dianggap menyempitkan tanggung jawab ke tingkat individu,21 sementara pertanggungjawaban untuk penindasan di masa modern jelas melampaui batasan tanggung jawab individual. Namun, peradilan transisional kontemporer menengahi dua kutub individual-kolektif ini melalui konstruksi hukum mengenai motif dan kebijakan. Dalam hal ini, interaksi antara konstruksi hukum maupun sejarah tentang pertanggungjawaban mendukung suatu pandangan yang kompleks tentang pelanggaran yang dilakukan individu dalam masyarakat yang berubah. Perkembangan hukum ini bersesuaian dengan meningkatnya Lihat Michael R. Marrus, The Holocaust in History, Hanover, N.H: University Press of New England, 1987, 36-51 (tinjauan sejarah tentang perubahan dari intensionalis ke fungsionalisme, namun tidak mengaitkannya dengan perkembangan hukum); Lawrence Douglas, “The Memory of Judgment: The Law, the Holocaust and Denial”, History and Memory, (musim gugur-dingin 1996): 100. Tentang perubahan pemahaman sejarah tentang pertanggungjawaban pidana, lihat Raul Hilber, Perpetratos, Victims and Bystanders, New York: Aaron Asher Books, 1992. 20 Lihat bab 2, catatan kaki 44. Lihat juga Public Prosecutor v Menten (Belanda, Proceedings from December 1977-January 1981), diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 12 (Alphen a.d. Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1981). Untuk pembicaraan lebih mendalam tentang pengadilanpengadilan tersebut, lihat bab 2 tentang peradilan pidana. Untuk tinjauan tentang perkembangan hukum tersebut, lihat Ronnie Edelman et al., “Prosecuting World War II Persecutors: Efforts at an Era’s End”, Boston College Third World Law Journal 12 (1991): 199. 21 Lihat Robert Goron, “Undoing Historical Injustice”, dalam Austin Sarat dan Thomas R. Kearny (eds.), Justice and Injustice in Law and Legal Theory, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. 19 7 pemikiran tentang semakin diperlukannya intervensi kemanusiaan, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang tanggung jawab moral dan hukum terhadap kekejaman. Terlepas dari apakah dalam hal ini hukum membentuk sejarah atau sebaliknya, dinamika keseluruhannya tampak dengan jelas – bahwa pemahaman hukum dan sejarah mengalami pergerakan ke arah yang sama. Pada akhir abad ke-20, terdapat anggapan bahwa tanggung jawab untuk penindasan di masa modern terletak pada individu, yang dilatarbelakangi oleh kebijakan yang sistemik. Pemahaman sejarah ikut berubah dengan merujuk pada kerangka yang diterima. Maka, nilai sejarah pengadilan pasca-perang juga ikut berubah sejalan dengan pemahaman di atas. Pandangan bahwa pengadilan tersebut diarahkan untuk menentukan tanggung jawab individual terhadap kejahatan perang telah berganti dengan pemahaman yang lebih kompleks tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam negara dengan sistem kedaulatan hukum yang modern, pengadilan merupakan ritual untuk secara terbuka mengkontekstualkan dan mengisahkan pengalaman pelanggaran di masa lalu. Dalam masa transisi, pengadilan memiliki peran yang bahkan lebih signifikan, karena ia tepat untuk digunakan merepresentasikan sejarah yang kontroversial, yang lazim terjadi pada masa gejolak politik. Namun, ritual-ritual tentang perdebatan sejarah kasus demi kasus, sebagaimana dilakukan oleh proses pengadilan terhadap individu, sering kali gagal menyikapi kekejaman besar-besaran yang merupakan ciri khas penindasan dalam negara modern. Dilema Keadilan Politis Pengadilan-pengadilan suksesor menunjukkan bahwa dalam saat transisi, pengadilan bisa digunakan sebagai kerangka pemahaman tentang tanggung jawab. Maka, meskipun pengadilan lazimnya dianggap menekankan pada tanggung jawab individual terhadap kesalahannya, pengadilan transisional menengahi pemahaman tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif. Meskipun pengadilan suksesor berpotensi untuk menciptakan suatu rekaman sejarah tentang masa lalu yang gelap suatu negara, penggunaan pengadilan untuk tujuan tersebut menjadi tantangan bagi prinsip kedaulatan hukum. Timbul dilema yang sukar ketika kebijakan penghukuman diterapkan terutama untuk menciptakan suatu rekaman sejarah, bila tujuan utama hukuman di masa transisi berada di luar sistem peradilan pidana di masa normal. Ilustrasi kontemporer tentang hal ini adalah penggunaan pengadilan pasca-komunis, seperti tentang pemberontakan Hungaria 1956, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masa sejarah yang semula kabur. Pengadilan-pengadilan tersebut berisiko dianggap dipengaruhi oleh kepentingan politik. Penyusunan sejarah publik dengan menggunakan hukum pidana menimbulkan kecemasan tentang dikorbankannya hak-hak individual terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan suatu catatan sejarah. Suatu kasus yang ekstrem adalah pengadilan seorang yang tidak bersalah untuk menunjukkan satu titik dalam sejarah. Penggunaan pengadilan untuk kepentingan politis secara terang-terangan demikian hanya akan menjadi “pengadilan sandiwara”. Bila negara-negara yang sedang mendemokratiskan dirinya menggunakan pengadilan untuk mencapai keadilan historis, mereka berisiko mengalami politisasi – dan memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan dibandingkan rezim sebelumnya. Bahkan bila pengadilan ditujukan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih liberal dan menaati prosedur hukum, begitu mulai dilaksanakan, dampak pengadilan sering 8 kali tidak dapat dikendalikan. Arah penggambaran sejarah melalui pengadilan tidak dapat diketahui sejak awal, paling tidak dalam sistem hukum adversarial [sistem hukum yang melibatkan pihak-pihak yang saling bertikai atau bertentangan], di mana prosesnya melibatkan tinjauan-tinjauan sejarah yang bertentangan: pengadilan untuk kepentingan sejarah bisa gagal menyampaikan pesan normatifnya tentang liberalisasi, dan malah menggagalkan tujuan pembangunan demokrasi yang sebenarnya ia emban. Suatu contoh yang terkenal adalah pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. Dengan mengadili Eichmann pada tahun 1961, pemerintah Israel berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah Holocaust bagi generasi pertama bangsa tersebut yang lahir dan besar di Israel. Meskipun pengadilan tersebut diusahakan untuk menunjukkan tanggung jawab Eichmann, proses tersebut tidak bisa mencegah timbulnya interpretasi sejarah lain yang lebih kontroversial, seperti tanggung jawab para kolaborator di kalangan masyarakat Yahudi sendiri, yang dikisahkan oleh Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.22 Demikian pula, ketika Klaus Barbie, sang “penjagal dari Lyons”, diadili di Prancis pada tahun 1988, publik berharap bahwa pengadilan tersebut akan memberikan gambaran jelas tentang sejarah Prancis di masa pendudukan. Memang benar bahwa pengadilan tersebut memberikan dramatisasi sejarah masa perang. Berbagai pihak, termasuk lebih dari 30 kelompok korban, kelompok perlawanan dan kelompok komunis ikut serta dalam pengadilan dan menggunakan proses tersebut untuk menceritakan pengalaman mereka tentang pendudukan. Para “saksi umum” tersebut tidak memberikan kesaksian tentang peristiwaperistiwa spesifik, sebagaimana lazimnya dalam pengadilan, namun memberikan interpretasi mereka tentang sejarah perang, menimbulkan persepsi bahwa tujuan pengadilan tersebut adalah untuk membantu menyatukan identitas politik Prancis yang retak. Pada akhirnya, pengadilan tersebut memang memiliki dampak terhadap pemahaman sejarah Prancis di masa perang, namun sebagaimana halnya dengan pengadilan Eichmann, hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Pembelaan Barbie terhadap tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dijawabnya dengan tuduhan balik bahwa Prancis melakukan hal serupa di Aljazair, sehingga beberapa pakar menilai bahwa pengadilan tentang kolaborasi Nazi ini bergeser menjadi genosida komparatif yang amat buruk (“Anda juga melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan”). Bahkan kesaksian pihak-pihak individual tersebut tampaknya mendukung pandangan universalis tentang penindasan masa perang, yang populer di kalangan kaum kiri Prancis. Pada akhirnya tinjauan, sejarah yang dielaborasikan dalam pengadilan Barbie gagal menyampaikan tujuan politik yang lebih luas, dan hanya memberikan suatu pesan berpihak yang sempit.23 Kejadian-kejadian tersebut menunjukan potensi politisasi dalam penggunaan pengadilan untuk mengkonstruksikan pemahaman sejarah transisional. Masalahnya timbul dari usaha merespon terhadap kejahatan yang dilakukan dalam konteks politik, melalui caracara juridis yang secara eksplisit dirancang untuk menciptakan suatu laporan resmi dari sejumlah versi sejarah yang bertentangan. Batasan ini menyulitkan penggunaan pengadilan Lihat Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York: Penguin Books, 1964, 135-50. 23 Lihat Alain Finkielkraut, Remembering in Vain: The Klaus Barbie Trial and Crimes against Humanity, (terjemahan Roxanne Lapidus dan Sima Godfrey), New York: Columbia University Press, 1992. Lihat juga Richard J. Golson (ed.), Memory, the Holocaust and French Justice: The Bousquet and Touvier Affairs, Hanover, N.H: University Press of New England, 1996 (tentang pengadilan pasca-perang lainnya); Guyora Bider, “Representing Nazism: Advocacy and Identity at the Trial of Klaus Barbie”, Yale Law Journal 98 (1989): 1321. 22 9 untuk penciptaan sejarah. Seperti dibicarakan di muka, respon yang lazim adalah penggunaan proses pidana yang terbatas yang tidak membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada individu, namun bisa membuat catatan untuk publik. Sanksi pidana terbatas ini memenuhi kepentingan untuk penyidikan dan dokumentasi, karena dilakukan secara formal oleh badan peradilan yang netral, dengan standar pembuktian tinggi seperti dalam proses hukum. Bahkan bila tidak ada pembebanan tanggung jawab individual, sanksi terbatas bisa memajukan rekaman sejarah dan konstruksi pengetahuan bersama tentang penindasan di masa lalu. Sanksi terbatas dapat mencapai kepentingan epistemik hukum pidana. Terlebih lagi, bila dikonstruksikan dalam konteks juridis, pengetahuan bisa membebaskan: bila proses pengadilan secara simbolis mengisolasikan kesalahan individu, masyarakat secara keseluruhan dibebaskan dari kesalahan. Penghilangan dan Repesentasi Masa-masa represif sering kali dilihat sebagai lembaran hitam dalam sejarah suatu bangsa. Anggapan tersebut paling jelas terlihat di Amerika Latin setelah masa pemerintahan militer dan kebijakan penghilangan di seluruh wilayah benua tersebut. Transisi di wilayah Amerika terjadi setelah puluhan tahun kediktatoran militer dan represi yang brutal, yang mencakup penculikan, penahanan, penyiksaan dan penghilangan secara luas, yang semuanya dilakukan atas nama “keamanan nasional” secara rahasia. Pengungkapan sejarah masa lalu yang terjadi pada masa transisi memperlihatkan betapa dalamnya kejahatan negara yang ditandai secara khas dengan apa yang diistilahkan “impunitas”. Kendatipun model penghilangan di Amerika Latin tampaknya memberikan definisi baru bagi impunitas, namun kebijakan penghilangan – seperti di Argentina – merujuk pada kebijakan fasis masa Perang Dunia Kedua untuk menahan dan melenyapkan para lawan politik “tanpa jejak”, untuk menghancurkan lawan politik dan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Bayangkan apa yang terjadi bila tubuh korban kejahatan dilenyapkan – mungkinkah kejahatan tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi? Penghilangan berarti bukti utama kejahatan, tubuh si korban, tidak dapat ditemukan.24 Michel Foucault menganggap “tubuh ... secara langsung terkait dengan lingkup politik; penguasa mengendalikannya; mereka berinvestasi pada tubuh, menandai tubuh, melatih tubuh, menyiksa tubuh.”25 Selain bentukbentuk kontrol sosial tersebut, penindasan di Amerika Latin pada dekade 1970-an menunjukkan kekuasaan negara yang koersif – menghilangkan tubuh korban, melenyapkan warga negara, menjadikan mereka apa yang kini dikenal desaparecidos (orang hilang). Selama pemerintahan militer di Argentina, lebih dari 10 ribu orang diculik, ditahan dan disiksa, dan akhirnya dihilangkan tanpa jejak. Seperti juga kerahasiaan dalam penculikan dan penahanan, penghilangan korban merupakan hal yang endemis pada kejahatan impunitas ini. Semua langkah tindakan militer – penculikan, penahanan, penyiksaan dan akhirnya pembunuhan – tidak bisa dibuktikan karena korban telah dihilangkan. Selama si korban tetap tidak Untuk penjelasan mendetail tentang praktik penghilangan, lihat Nunca Más: Report of the Argentine National Commission on the Disappeared (seterusnya disebut saja sebagai laporan CONADEP), edisi bahasa Inggris, New York: Farrar, Strauss, Giroux, 1986, 447. Laporan CONADEP menyimpulkan bahwa banyak mayat yang dimusnahkan untuk mencegah identifikasi. 25 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (terjemahan Alan Sheridan), New York: Vintage Books, 1979, 25. 24 10 ditemukan, militer tetap berjaya dan mempertahankan kekuasaannya. Penghilangan warga negara merupakan pelaksanaan kekuasaan pada bentuknya yang paling keji dan kejam. Ketika rezim berganti dengan rezim yang memerdekakan, para korban yang dihilangkan menjadi lambang pengalaman kediktatoran. Mereka yang dihilangkan adalah korban yang tidak berdaya; hilang pulalah politik tubuh yang tampaknya lenyap dalam jepitan represi militer, juga negara yang lama. Penghilangan adalah kejahatan yang memiliki sifat tidak pasti. Apakah bila negara gagal menjelaskan nasib para korban dan menemukan mereka, berarti kejahatan tersebut terus terjadi dan tidak berakhir? Penghilangan menimbulkan pertanyaan tentang apakah rezim penerus tetap harus bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Terdapat pilihan yang sukar antara keadilan atau impunitas, antara menghukum militer atau membiarkan masa lalu terus berjalan. Apakah kesetimbangan kekuasaan yang rapuh dan ketidakmampuan untuk menghukum militer berarti sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi para korban dan mereka yang selamat untuk mendapatkan penyelidikan pidana terhadap kasus-kasus mereka? Apakah tidak menghukum berarti sama dengan tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan di masa rezim pendahulu dan bahwa negara terus terlibat dalam kesalahan tersebut, utamanya kebijakan penghilangan? Pertanyaan sukar yang dihadapi banyak negara yang baru beranjak dari pemerintahan represif adalah bagaimana menghadapi lembaran hitam sejarah yang ditimbulkan oleh impunitas negara yang mencirikan penindasan di masa modern. Bagaimana cara merespon kebijakan penghilangan? Bagaimana cara menentukan apa yang terjadi pada sejumlah besar orang yang dihilangkan dan dibunuh, yang terjadi karena pembunuhan administratif, oleh aparat keamanan modern, dan bagaimana cara melaporkan kekejaman tersebut? Penggunaan pengadilan secara terbatas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang sedemikian luas membuat sistem peradilan pidana tidak mampu menghadapinya. Demikian pula, respon masyarakat terhadap penghilangan menunjukkan perkembangan sistem respon yang baru: respon birokratis terhadap pembunuhan birokratis. Bagaimana menentukan kejahatan “impunitas”? Bagaimana cara membuktikan apa yang terjadi pada masa pemerintahan represif, ketika kebijakan penghilangan berarti korbankorban yang dilenyapkan, saksi-saksi yang ketakutan dan pemerintah yang menutupi semua kejadian tersebut? Masalah pembuktian mengarah pada pembentukan apa yang kini dikenal sebagai komisi kebenaran.26 Lingkup penyidikan komisi kebenaran sesuai untuk menentukan fakta-fakta berkaitan pembunuhan massal oleh birokrasi, dengan skala kekerasan yang besar, dengan jumlah peristiwa yang mencapai puluhan ribu. Komisi penyidikan demikian menjadi mekanisme terpenting untuk menyikapi kejahatan negara penindas modern, karena pembunuhan birokratik memerlukan lawannya dalam bentuk institusional yang sebanding, suatu respon yang bisa menggambarkan kebijakan penindasan yang masif dan sistemik. Bila mereka yang selamat dan para sanak korban yang dihilangkan menuntut agar rezim penerus mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi pada masa pemerintahan junta, tuntutan mereka mendorong pembentukan komisi penyidikan. Mandat Komisi Nasional Orang Hilang (CONADEP) adalah untuk menentukan kebenaran tentang nasib mereka yang dihilangkan dan tentang penindasan, namun tidak untuk menjawab pertanyaan tentang apa tindakan perbaikan yang kemudian akan dilakukan. Meskipun kelompok-kelompok korban membuat petisi agar komisi tersebut dibuat oleh pemerintah, CONADEP merupakan 26 Untuk daftar yang lengkap, lihat Priscilla Hayner, “Fifteen Truth Commission – 1974 to 1994, A Comparative Study”, Human Rights Quarterly 16 (1994): 597. 11 kompromi politik dan hanya setengah resmi. Tanpa kekuasaan pidana, komisi tersebut lebih merupakan badan pencari fakta, alih-alih penyidik; mandatnya adalah untuk melaporkan apa yang terjadi pada masa pemerintahan militer. Setelah sembilan bulan, sebuah laporan yang panjang lebar mengidentifikasi nama-nama mereka yang dihilangkan, siapa yang dianggap telah mati, dan mendokumentasikan sifat sistematis dari penindasan oleh junta militer tersebut. Meskipun laporan tersebut menyebutkan nama-nama para korban, ia tidak menyebutkan nama pelaku, yang menimbulkan kontroversi. Namun, tanggung jawab dibebankan kepada berbagai cabang dalam junta militer, dan pembebanan tanggung jawab ini kemudian menjadi dasar untuk proses pidana terhadap para komandan militer.27 Komisi kebenaran sebagai respon terhadap penindasan militer masa lalu segera ditiru oleh negara-negara lainnya. Di semua negara yang mengalami transisi dari pemerintahan militer yang brutal, timbul pertanyaan penting tentang apakah kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu akan dilupakan begitu saja. Komisi kebenaran timbul sebagai jawaban terhadap impunitas, dan berjalan seiring dengan amnesti. Di seluruh wilayah Amerika – di Argentina, Cili, El Salvador, Honduras, Haiti dan Guatemala – tempat terjadinya kekerasan besar-besaran terhadap penduduk, yang mengecilkan kemungkinan keberhasilan respon pidana, komisi kebenaran menjadi mekanisme sentral dalam transisi politik.28 Dalam usaha untuk melakukan perubahan politik menuju sistem liberal di Cili, respon rezim penerus terhadap pemerintahan militer yang represif di masa lalu adalah melalui penyelidikan sejarah oleh Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi.29 Penyelidikan, yang dibatasi pada penemuan fakta-fakta tentang kebijakan penghilangan oleh militer, mencapai kesimpulan bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi ribuan warga sipil. Ketika perang saudara di El Salvador, yang memakan hingga 75 ribu korban tewas dan ribuan lainnya terpaksa berpindah tempat tinggal, dan berlangsung selama sekitar sepuluh tahun, akhirnya selesai, kesepakatan perdamaian akhirnya mensyaratkan pembentukan “komisi kebenaran” internasional untuk menyelidiki pelanggaran di masa lalu. Komisi yang dibentuk setelah konflik berkepanjangan sebagai hasil kesepakatan damai ini memiliki mandat untuk mendokumentasikan “pelanggaran berat” oleh pasukan pemerintah maupun anti pemerintah selama perang saudara yang berkepanjangan ini.30 Untuk pertama kalinya sejak transisi pasca-Perang Dunia Kedua, penyelidikan netral terhadap pelanggaran yang dilakukan suatu negara dijalankan oleh suatu badan internasional. Serupa dengan itu, kesepakatan damai di Guatemala, setelah perang selama 36 tahun yang menewaskan atau menghilangkan ratusan ribu orang, berhasil dicapai setelah ada Lihat Human Rights Watch, An Americas Watch Report: 13-17. “Komisi Klarifikasi Sejarah Masa Lalu” di Guatemala disepakati pada tanggal 23 Juni 1997 di Oslo, Norwegia. Lihat juga Accord on the Establishment of the Commission for Historical Clarification of Human Rights Violations and Acts of Violence Which Have Inflicted Suffering upon the Guatemalan Population (Guatemala, 1997); Popkin dan Roht-Arriaza, “Truth as Justice”, 79-116. 29 Komisi Kebenaran Cili ditetapkan dengan Ketetapan No. 355. “Hanya pada dasar kebenaran kita dapat memenuhi tuntutan mendasar akan keadilan dan menciptakan kondisi yang tidak dapat diabaikan untuk mencapai rekonsiliasi nasional sepenuhnya” (25 April 1990). Lihat José Zalaquett, Pengantar Informe de la Comisíon Nacional de Verdad y Reconciliation (Laporan Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili) (terjemahan Philip E. Berrymann, dua jilid), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993, xxiii-xxxiii. 30 Lihat United Nations Observer Mission in El Salvador, El Salvador Agreements: The Path to Peace (1992), 16-17 (memberikan sinopsis kesepakatan antara pemerintah El Salvador dan Frente Farabundo Marti para la Liberacíon Nacional (FMLN) di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB). 27 28 12 kesepakatan untuk mencari kebenaran.31 Komisi Klarifikasi Sejarah menemukan penindasan rasial dan bahkan genosida. Di Honduras, setelah lebih dari satu dekade penghilangan, Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1992 untuk mengadakan penyelidikan. Laporan komisi ini pada tahun 1994 menemukan hampir 200 kasus penghilangan dan menyebutkan nama beberapa perwira tinggi militer sebagai pelaku kejahatan tersebut.32 Di Haiti, Komisi Nasional Kebenaran dan Keadilan dibentuk pada tahun 1995 untuk menentukan kebenaran tentang pelanggaran-pelanggaran sangat serius terhadap hak asasi manusia yang dilakukan antara tahun 1991-1994 secara domestik maupun di luar negeri, dan untuk membantu proses rekonsiliasi para warga Haiti.33 Seperti di wilayah Amerika, di Afrika, setelah pemerintahan represif dan dalam konteks tumbuhnya demokrasi yang masih rapuh, dibentuklah komisi-komisi di Uganda, Chad dan Afrika Selatan pasca-apartheid.34 Uganda membentuk sebuah komisi penyelidikan pada tahun 1986, setelah dua dekade kekejaman di bawah rezim Idi Amin dan Milton Obete, yang menewaskan hampir sejuta jiwa. Keserupaan antara pertanggungjawaban sejarah dan pidana tampak dalam hasil-hasil penelitian dan dokumentasi cermat tentang kejadian-kejadian bermasalah, hasil penyelidikan komisi kebenaran, juga dalam penentuan tanggung jawab individual. Misalnya di Chad, setelah jatuhnya rezim Habré pada tahun 1990, sesuai anjuran organisasi-organsisasi internasional, ditunjuklah sebuah komisi penyidikan untuk meneliti dan melaporkan kekejaman yang dilakukan oleh rezim tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa sekitar 40 ribu orang disiksa dan dieksekusi oleh aparat keamanan Habré. Laporan dokumentasi tersebut memiliki keserupaan dengan sanksi pidana, yaitu dalam aspek pencatatan dan stigmatisasinya: para pelanggar diidentifikasi, dan bahkan foto para pelaku dimuat dalam laporan.35 Pelaksanaan penyelidikan administratif sebagai alternatif terhadap hukuman juga dilakukan di Afrika Selatan. Penyelidikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan terhadap apartheid disepakati untuk dilakukan sebagai bentuk kebijakan non-retributif. Amnesti akan diberikan sebagai pertukaran kerja sama dalam proses kerja komisi kebenaran.36 Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang jumlahnya berjilid-jilid itu membahas “terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia oleh semua pihak yang berkonflik”, dan juga struktur sejarah, institusional dan sosial yang lebih luas dari sistem apartheid. Dalam suatu masyarakat yang amat terpecah belah, kebenaran akan dijadian dasar bagi rekonsiliasi. Bila tidak terdapat dorongan politik untuk melakukan penyelidikan resmi, konstruksi ingatan kolektif dan penyelidikan serta dokumentasi penindasan di masa lalu dilakukan oleh 31 Lihat Robert F. Lutz, “Essay: A Peace of the Peace: The Human Rights Accord and the GuatemalanPeace Process”, Southwestern Journal of Trade and Law in Americas 2 (1995): 183. 32 Lihat Human Rights Watch, The Preliminary Report on Disappearance of the National Commissioner for the Protection of Human Rights in Honduras: The Facts Speak for Themselves, New York: Human Rights Watch, 1994. 33 Order (Arréte) of March 28, 1995, membentuk “Commission Nacional de Verité et de Justice”. 34 Lihat Lynn Berat dan Yossi Shain, “Retribution or Truth-Telling in South Africa? Legacies of the Transitional Phase”, dalam Kader Asmal dan Ronald Suresh Roberts (eds.), Law and Social Inquiry 20 (1995): 163; Reconciliation through Truth: A Reckoning of Apartheid’s Criminal Governance, New York: St. Martin’s, 1997. 35 Untuk penjelasan tentang komisi Uganda dan Chad, lihat Jamal Benomar, “Coming to Terms with the Past: How Emerging Democracies Cope with a History of Human Rights Violations” (makalah dipresentasikan di Carter Center, Emory University, Human Rights Program, Juli 1992), 11-14. 36 Lihat Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, Juta’s statutes of the Republic of South Africa, jilid 1 (1997), 801. 13 organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, seperti oleh gereja. Komunitas yang paling banyak menjadi korban penghilangan di wilayah Amerika mungkin adalah komunitas Maya di Guatemala. Sebelum berakhirnya perang selama tiga dekade, penyelidikan dilakukan oleh sebuah organisasi gereja, REHMI Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Kantor Hak Asasi Manusia Keuskupan Agung) atau disebut juga ODHA. Laporan tidak resminya, dengan mandat untuk “mengembalikan ingatan sejarah”, berdasar pada pengakuan para korban, diharapkan untuk digabungkan dengan laporan resmi yang diharapkan akan disusun setelah berakhirnya perang.37 Temuan tidak resmi tentang penindasan rasial ini mengguncangkan seluruh negeri, dan kemudian dikonfirmasikan oleh laporan resmi, “Ingatan tentang Kebisuan” (The Memory of Silence). Di wilayah lain di benua tersebut, bila pemerintahan militer berakhir tanpa transisi politik yang jelas, seperti di Brazil, atau setelah negosiasi yang berlarut-larut, seperti di Uruguay, penyelidikan oleh pemerintah tidak dapat dilakukan. Di Brazil, penyelidikan terhadap pelanggaran di masa lalu dilakukan oleh para rohaniwan, yang menulis laporan berjudul “Tidak Akan Pernah Lagi” (Never Again) berdasar arsip yang secara rahasia “dicuri” dari militer. Hingga hari ini, laporan ini merupakan satu dari amat sedikit catatan tentang represi militer Brazil pada dekade 1970-an, dan telah disebarluaskan di seluruh negeri.38 Meskipun usaha penemuan kebenaran Brazil dan Uruguay tidak dilakukan oleh pemerintah, mereka meniru usaha pencarian kebenaran resmi di wilayah tersebut, seperti Argentina, dan menunjukkan bagaimana pelaporan oleh pihak nonpemerintah pun dapat dianggap sebagai kebenaran sosial apabila ia mengikuti bentuk transisional yang baku. Baik laporan Brazil maupun Uruguay memilik bentuk yang serupa dengan laporan pemerintah yang resmi. Dengan judul Nunca Más atau Never Again, laporan tersebut mengikuti model laporan Argentina: dalam judul, sistematika, mandat penyelidikan dan sumber-sumber bukti, yang berasal dari sumber resmi pemerintah. Dengan cara ini, bahkan laporan “tidak resmi” pun dapat dikatakan menghasilkan kebenaran yang “resmi”. Laporan Brazil, yang seluruhnya bersumber pada arsip pemerintah, meskipun bukanlah catatan pengadilan, pada dasarnya merupakan pengakuan negara terhadap pelanggaran yang dilakukannya, yang didapatkan oleh para rohaniwan penting Brazil. Dan, karena penindasan di Uruguay dicirikan oleh penahanan melanggar hukum dan penyiksaan (bukan pembunuhan), ada korban yang selamat, sehingga para mantan tahanan bisa memberikan kesaksian sebagai bukti langsung dalam catatan sejarah.39 Dari namanya – Nunca Más – bahasa Spanyol yang berarti “tidak akan pernah lagi”, laporan-laporan kebenaran Amerika Latin diarahkan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan, yang biasanya merupakan tujuan penghukuman.40 Pencegahan kemungkinan terjadinya kejadian di masa depan pada umumnya merupakan justifikasi utama untuk penghukuman, namun dalam masa transisi, kepentingan kedaulatan hukum dapat dicapai dengan cara-cara alternatif – penyelidikan administratif, misalnya. Popularitas Lihat Rigoberta Menchú, I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala, (Editor: Elizabeth BurgosDebrany, penerjemah: Ann Wright), London: Verso, 1984. 38 Untuk tinjauan demikian, lihat Lawrence Weschler, A Miracle, A Universe: Settling Accounts with Torturers, New York: Penguin Books, 1991. 39 Lihat Servicio Paz y Justicia, Uruguay, Nunca Más: Human Rights Violations, 1972-1985, terjemahan Elizabeth Hampsten dengan pengantar oleh Lawrence Weschler, Philadelphia: Temple University Press, 1992, xxv. 40 Nunca Más adalah judul laporan Argentina dan Uruguay; sementara laporan Brazil berjudul Nunca Mais. 37 14 penyelidikan demikian sebagai alternatif peradilan pidana menunjukkan keserupaan antara bentuk-bentuk pidana dan administratif dalam transisi. Kebenaran yang Diciptakan: Epistemologi Kebenaran Resmi Pertimbangkanlah bagaimana cara penyelidikan dalam masa transisi bisa memberikan gambaran tentang cara mendapatkan kebenaran resmi. Penggunaan komisi kebenaran – bukan pengadilan tradisional, namun merupakan bentuk penyelidikan setengah resmi – menantang intuisi kita tentang sifat dan bentuk keadilan historis. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, epistemologi kebenaran transisional berkaitan erat dengan struktur administratif, kekuasaan dan proses-proses dalam komisi kebenaran. Pengetahuan publik tentang masa lalu diciptakan melalui proses panjang representasi oleh para pelaku, korban dan masyarakat luas, memberikan dasar bagi penyelidikan sejarah dengan konsensus sosial. Kebenaran tersebut dicapai secara bersama-sama dan dilegitimasi melalui proses non-adversarial, yang mengaitkan pertimbangan sejarah dengan potensi konsensus. Mandat komisi kebenaran merupakan kompromi yang tegas terhadap isu penting dalam keadilan transisional, yaitu “pengadilan atau impunitas”. Seperti penuntutan di pengadilan, kepada komisi-komisi setengah resmi ini didelegasikan kekuasaan oleh eksekutif, yaitu yaitu kekuasaan melakukan penuntutan. Namun, kendatipun beberapa komisi kebenaran memiliki kekuasaan penyelidikan yang luas, seperti kekuasaan untuk men-subpoena – seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan – tidak ada yang memiliki kekuasaan yudisial sepenuhnya. Konstruksi kebenaran publik yang dapat dipercaya bergantung pada proses ratifikasi lainnya di luar pemerintah, yang ditimbulkan oleh rakyat. Kebenaran transisional yang dapat diterima secara sosial diciptakan dalam struktur demokrasi yang baru dibentuk, oleh dua narator: rakyat dan elite yang dipilih. Ketua komisi kebenaran biasanya dipilih dari warga negara yang dihormati karena integritasnya, suatu elite moral. Sebagai suatu badan, komisi tersebut diharapkan berimbang secara politis dan netral. Masalah netralitas ini terutama penting dalam transisi setelah perang saudara, sehingga misalnya komisi El Salvador beranggotakan wargawarga asing, yang berada di luar lingkup pertikaian golongan antara sesama warga El Salvador. Hal yang sama terjadi dalam Komisi Klarifikasi Sejarah di Guatemala. Terdapat anggapan bahwa kebenaran haruslah tidak memihak, dan dengan demikian berada di luar lingkup pertikaian domestik.41 Apa yang merupakan “sejarah resmi”? Jika para komisioner menjadi otoritas moral dengan membawakan suara netralitas, para korban memberikan otoritas moral dengan membawakan suara para korban, mereka yang mengalami penindasan oleh negara secara langsung. Para korban penindasan di masa lalu adalah sumber utama bukti dalam penyelidikan sejarah. Komisi kebenaran bergantung pada kesaksian para korban, dan mereka yang paling banyak menderita akibat negara menjadi para saksi yang paling bisa dipercaya. Bila kesaksian para korban dinarasikan oleh para komisioner yang merupakan aktor setengah resmi, kebenaran tersebut bisa menjadi milik bersama, suatu kisah nasional dan dasar konsensus transisional. Untuk pemikiran terkait, lihat Michel Foucault, The Birth of the Clinic, terjemahan A.M. Sheridan Smith, New York: Vintage Books, 1994. 41 15 Pengetahuan sosial tentang masa lalu dikonstruksikan oleh proses publik. Prosesproses tersebut menghasilkan kebenaran yang mendemokratiskan yang membantu membangun suatu konsensus kemasyarakatan. Proses-proses tersebut juga merupakan ritualritual kritis dan transformatif yang membalikkan kebijakan pengetahuan rezim yang lama. Sementara impunitas terjadi dalam masa pemerintahan represif yang lama, dan rezim militer dikenal karena menutup-nutupi kebenaran, pemerintahan yang baru dikenal karena ketaatannya pada hukum. Hak untuk melakukan dengar pendapat, yang secara tradisional merupakan bagian dari proses administratif, secara terbuka menegaskan hak partisipasi politik dan harga diri individual. Penyelidikan administratif bergantung pada partisipasi warga – yang didorong oleh negara melalui insentif yang kuat, seperti ganti rugi bagi para korban dan imunitas bagi para pelaku. Afrika Selatan memberikan contoh bagaimana struktur insentif yang tersirat dalam ketergantungan komisi administratif terhadap kesaksian dan pengakuan, yang dikaitkan dengan ganti rugi dan amnesti. Terlepas dari insentif-insentif tersebut, proses-proses pengungkapan pengalaman tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk katarsis. Jika rezim pendahulu gagal melindungi warganya dari pelanggaran oleh pasukan keamanan, dalam pemerintahan yang sedang melakukan liberalisasi, kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman di muka pemerintahan baru dapat mengembalikan sebagian dari harga diri yang dahulu dilanggar. Dampak kesaksian para korban menjadi lebih besar bila acara dengar pendapat komisi kebenaran dilakukan di tempat-tempat publik di mana terjadi penindasan sebelumnya. Proses publik ini juga memberikan legitimasi kepada rezim yang baru. Mereka yang sebelumnya disiksa dan dipaksa untuk membisu kini bisa secara terbuka mengungkapkan pengalaman mereka dalam masa penindasan.42 Kisah-kisah mereka yang selamat dibandingkan satu sama lain, dan pola-pola penindasan sistematis menjadi terlihat. Selain bukti-bukti lain, kisah-kisah tersebut menjadi penyusun kebenaran resmi. Kesaksian para korban dan saksi lainnya direkonstruksikan oleh para komisioner menjadi suatu kisah yang tunggal tentang penindasan negara. Laporan kebenaran resmi ini merupakan suatu bentuk narasi yang spesifik, sehingga tidak mengherankan bahwa para ketua komisi sering kali adalah pengarang terkenal, seperti Ernesto Sábato, ketua CONADEP Argentina. Penyelidikan kebenaran transisional diberikan mandat untuk menentukan “apa yang terjadi” dalam masa pemerintahan yang kejam. Praktik komisi kebenaran menunjukkan ketaatan pada prinsip-prinsip dokumentasi. Laporan-laporan kebenaran tersebut ditulis dalam gaya bahasa dokumentasi resmi. Perhatikanlah standar kepastian yang digunakan untuk menentukan “kebenaran resmi”. Hukum Amerika menekankan standar pembuktian sebagai karakteristik utama yang membedakan pencarian kebenaran pidana dan perdata. Namun, anggapan tentang standar pembuktian dan pelaporan ini menjadi aneh dari sudut pandang terhadap kebenaran dalam budaya hukum lainnya. Jadi, kebenaran menurut sistem hukum kontinental merupakan suatu pemahaman yang tunggal, tanpa memperhatikan proses hukum pidana atau perdata.43 Gabungan penyelidikan pidana dan perdata dalam komisi kebenaran transisional berusaha untuk menjalankan pendekatan tunggal serupa terhadap pertanyaan tentang standar pembuktian yang tepat. Ketika pertanyaan tersebut diajukan oleh komisi kebenaran El Salbador, ia menggunakan aturan dua-sumber, yang merupakan standar Lihat misalnya, Report of the Commission on the Truth for El Salvador (kemudian Laporan Komisi Kebenaran El Salvador) (April 1993), 229. Lihat juga Laporan CONADEP, 5. 43 Tentang kebenaran dalam sistem hukum kontinental, lihat Damaska, “Evidentiary Barriers”, 580. 42 16 pembuktian yang biasa digunakan oleh para sejarawan dan jurnalis. Standar pembuktian minimal, “cukup bukti”, berkorelasi dengan banyaknya bukti yang mendukung, dan dengan demikian membutuhkan lebih dari satu sumber.44 Laporan kebenaran bukanlah suatu tinjauan yang tergeneralisasi dan umum, namun merupakan catatan dokumentasi yang mendalam. Laporan biasanya memuat banyak detail: laporan-laporan itu mencatat penghilangan berdasarkan nama jalan tempat terjadinya penculikan, nama tempat penahanan, nama panggilan para penyiksa, nama tahanan yang lain, dan nama para saksi yang memberikan kesaksian.45 Semua detail dicatat secara verbatim. Dalam bahasa yang sederhana dan terus terang, hal-hal yang semula tidak dipercaya menjadi dapat dipercaya. Dengan semakin banyak detail, semakin banyak pula jawaban terhadap kebisuan negara di masa lalu. Semakin teliti dokumentasi, semakin sedikit variasi interpretasi atau bantahan yang dimungkinkan. Satu hal penting dalam sejarah transisional adalah bahwa kebenaran resmi haruslah diketahui hingga sedetail mungkin. Mengetahui dengan mendetail berarti menutup celah hal-hal di masa lalu yang karena kekejamannya dan dukungan negara, akan tidak dipercaya dan dilupakan. Kebenaran resmi tentang kejahatan negara harus ditentukan berdasarkan dokumentasi yang teliti, dan paradigma tentang pelaporan resmi tentang kekejaman negara adalah laporan dalam bentuk yang literal. Ritual pertanggungjawaban membalikkan praktik penghilangan, dan membatalkan kebijakan rahasia di masa lalu. Pelaporan secara literal merespon dan membatasi model narasi-narasi lain yang bertentangan. “Laporan” menjadi cara dominan untuk mengisahkan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman. Cara tersebut dapatlah dikatakan sebagai cara juridis.46 Politik Ingatan: Mengaitkan Rezim Sejarah dan Rezim Politik “My Dreams are like your vigils” (Jorge Luis Borges, A Personal Anthology) Agar suatu kebenaran dapat dianggap “resmi”, diperlukan konsensus demokratik. Namun dalam transisi, proses demokratik sering kali belum dikonsolidasikan dengan baik, dengan implikasi terhadap otoritas dan legitimasi penciptaan pengetahuan dalam masa transisi. Dengan demikian, dalam pencarian kebenaran masa transisi, ada usaha bersama untuk menjadikan pertanggungjawaban sejarah dan politis dapat berjalan seiring. Rezim kebenaran transisional tidak berdiri sendiri, namun terkait erat dengan proses-proses dalam penciptaan pengetahuan, selain narasi sejarah yang telah ada. Konsensus pada sejarah yang diciptakan didasarkan pada penyebarluasan dan penerimaan kebenaran di tingkat masyarakat. Dari mana sumber kekuasaan kebenaran resmi? Proses hukum presentasi dan ratifikasi memberikan otoritas dan legitimasi dalam proses demokrasi. Begitu selesai, laporan kebenaran diberikan kembali kepada aktor pemerintah yang memberikan kekuasaan kepada komisi kebenaran, Lihat Laporan Komisi Kebenaran El Salvador, 24. Laporan CONADEP, 49-51. Untuk kisah tentang sesi penyiksaan, dijelaskan secara mendetail oleh para korban, lihat Uruguay, Nunca Más, 102-03. 46 Untuk contoh, lihat Human Rights Watch, Annual Report, New York: Human Rights Watch, 1997. 44 45 17 biasanya eksekutif negara yang bersangkutan.47 Penyebarluasan informasi merupakan langkah berikutnya, misalnya di Cili, setelah presentasi laporan Komisi Rettig kepada presiden, laporan kemudian dipresentasikan kepada masyarakat luas.48 Proses serupa terjadi dalam presentasi laporan komisi internasional El Salvador kepada PBB.49 Ritual publik tentang pertanggungjawaban sering kali disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah, Misalnya, di Cili pasca-pemerintahan militer, presiden secara terbuka memaparkan hasil temuan komisi kebenaran kepada seluruh masyarakat, di sebuah stadion olahraga, yang semula pernah digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan. Hal ini menggambarkan sekali lagi bahwa ritual-ritual kritis tersebut merupakan suatu pembalikan – penggunaan ritual-ritual represi dari masa lalu – terhadap ritual di masa lalu, dengan tujuan untuk memberikan arti baru. Dalam presentasinya, Presiden Patricio Aylwin menyatakan bahwa penghilangan merupakan “eksekusi” yang dilakukan oleh “agen-agen negara”, secara formal mengakui tanggung jawab negara dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat.50 Presiden Aylwin “mewakili seluruh negara, dan atas namanya, mengakui tanggung jawab negara, kepada para korban”.51 Permintaan maaf transisional ini memberikan rehabilitasi secara terbuka bagi para korban, yang telah direndahkan oleh rezim lama, yang mengatangatai mereka sebagai “musuh negara”. Tindakan ini memiliki konsekuensi di tingkat masyarakat, yang jauh lebih besar daripada permintaan maaf secara informal, dan menunjukkan kedekatan antara keadilan historis dan reparatoris. Sementara dengan permintaan maafnya, presiden mewakili negara dan seluruh tanggung jawabnya kepada para korban, ia juga menegaskan kebutuhan terhadap “tindakan pengakuan terhadap penderitaan” yang dialami seluruh bangsa. Representasi kebenaran secara publik, melalui lembaga eksekutif, memberikan ekspresi tentang pertanggungjawaban politik masa transisi dan menggambarkan dilema tanggung jawab suksesor dalam masa transisi. Ketika rezim kebenaran baru dipresentasikan, dan wakil rezim baru meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas nama negara untuk tindakan-tindakan yang dilakukan pada masa pemerintahan yang lama, terlihat adanya kontinuitas negara dan kedaulatan hukum. Apologi transisional memberikan kontinuitas tanggung jawab negara, sekaligus merupakan diskontinuitas – melepaskan masa lalu. Tentu saja permintaan maaf resmi memainkan peranan dalam mengakui kesalahan yang dilakukan pemerintah. Permintaan maaf oleh eksekutif merupakan bentuk pengakuan resmi oleh pemerintah tentang kesalahannya di masa lalu, terutama dalam lingkup hubungan internasional.52 Sementara ini merupakan praktik umum dalam tingkat negara, pengalaman transisional menunjukkan penggunaan tindakan ini pada tingkat domestik, antara pemerintah baru dan warga negaranya. Sebagai puncak usaha pencarian kebenaran, permintaan maaf transisional berperan serta dalam menggerakan pergeseran rezim politik. 47 Meskipun di Afrika Selatan wewenang diberikan oleh parlemen, laporan akhir diserahkan kepada Nelson Mandela. 48 Lihat Informe Rettig, Informe de la Comisíon Nacional de Verdad y Reconciliation, (Februari 1991) (selanjutnya disebut saja Laporan Rettig), xxxii. 49 Lihat Julia Preston, “2,000 Salvadoreans Helped UN Build Atrocities Case”, Washington Post, 16 Maret 1993. 50 Pidato Presiden Patricio Aylwin kepada rakyat Cili, ditranskripkan oleh British Broadcasting Corporation, 5 Maret 1991. 51 El Murano, 5 Maret 1991. 52 Untuk perspektif sosiologis tentang pentingnya permintaan maaf, lihat umumnya Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation, Stanford University Press, 1991. 18 Jika mandat komisi kebenaran adalah untuk menentukan apa yang terjadi pada masa pemerintahan yang lama, maka semata-mata mengumpulkan fakta belumlah memenuhi mandat ini. Yang sedang dipermasalahkan adalah sejarah suatu bangsa yang masih belum jelas. Dengan demikian, komisi kebenaran, seperti juga pengadilan suksesor, adalah forum pertanggungjawaban sejarah publik tentang peristiwa-peristiwa traumatik, karena transisi berarti pergeseran atau pergantian rezim kebenaran. Dalam pergeseran dari pemerintahan militer, kebenaran yang sedang dipermasalahkan adalah tentang karakter kekerasan pada masa pemerintahan sebelumnya. Dalam kisah versi militer, kekerasan yang ia lakukan adalah “perang”, mereka yang dihilangkan adalah “gerilyawan”, dan represi dijustifikasi sebagai “perang terhadap pemberontak”. Pengisahan inilah yang dicoba dijawab oleh laporan kebenaran transisional, memberikan kebenaran dari pihak suksesor sebagai pengganti kebenaran versi rezim lama.53 Mengubah anggapan lama tentang tindakan negara dimungkinkan melalui “kategorisasi” dan “emplotment” dalam narasi yang baru. Kategorisasi dan emplotment adalah cara-cara dalam narasi transisional untuk memberikan gambaran baru dan legitimasi baru terhadap kisah-kisah tentang masa lalu. Agar tindakan negara di masa lalu dianggap tidak sah, perlu pelaporan fakta-fakta dengan cara sedemikian rupa sehingga perbedaan-perbedaan relevan menjadi terlihat, melalui penggunaan kategori paralel, dalam konteks pemerintahan represif di masa lalu. Sebagai contoh, laporan Cili disusun berdasarkan kategori tindakan negara, membedakan korban “kekerasan politik” dari korban “pelanggaran hak asasi manusia”.54 Representasi kedudukan dan tindakan para pelaku dan korban menjadi elemen untuk rekonstruksi representasi pelanggaran-pelanggaran di masa lalu yang telah ada. Apa yang terjadi pada masa pemerintahan yang lama direpresentasikan dalam perubahan kategori kekerasan. Selain fakta-fakta yang baru ditemukan, terdapat renegosiasi terhadap representasi bahasa kekerasan politik: “konflik bersenjata”, “pemberontakan”, “terorisme politik”, “kejahatan terhadap kemanusiaan”, dan “genosida”. Transformasi sejarah terjadi melalui representasi eksplisit dalam bentuk rekategorisasi fakta-fakta kontroversial – terutama sifat dan justifikasi kekerasan politik di masa lalu. Sebagai contoh, dalam transisi dari pemerintahan militer, kebenaran yang kritis adalah yang berkaitan dengan keamanan nasional negara dan doktrin-doktrinnya. Laporan suksesor memberikan respon yang kritis terhadap klaim rezim militer pendahulu dengan menyatakan bahwa kekerasan negara tidak bisa dijustifikasi oleh doktrin keamanan nasional dalam apa yang disebutnya perang melawan subversi, dan bahwa mereka yang dibunuh bukanlah teroris politik, melainkan warga negara biasa, dan penghilangan tidak bisa dijustifikasi atas alasan keamanan. Ketika laporan Nunca Más Argentina menyimpulkan bahwa seperlima jumlah korban penghilangan adalah pelajar,55 jadi mereka dikategorikan sebagai “warga sipil tidak bersenjata”, representasi demikian merupakan revisi yang kritis yang memaksakan perubahan atau transisi dalam rezim kebenaran. Representasi demikian melawan justifikasi kekerasan politik di masa lalu. Untuk alasan inilah, biasanya sebagian besar isi laporan komisi kebenaran memuat identifikasi dan kategorisasi para korban secara sistematis, dengan implikasi yang berat terhadap rezim lama. Dengan menyatakan bahwa para korban adalah warga sipil yang tidak bersenjata, dan bukan kombatan, laporan komisi kebenaran menolak rezim kebenaran militer dengan klaimnya Lihat Laporan CONADEP, 448-49. Lihat Laporan Rettig, 39-40. 55 Lihat Laporan CPNADEP, 448 53 54 19 bahwa ia melakukan perang melawan terorisme, dan dengan demikian menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah penindasan sistematis yang disponsori oleh negara. Namun usaha untuk menarik garis baru dalam penggolongan kekerasan politik yang dapat dijustifikasi membutuhkan kehati-hatian. Penggolongan itu memiliki banyak risiko politisasi, dan batasannya pun tipis, terutama bila yang hendak dibedakan adalah kekerasan politik dan kekerasan hak asasi manusia. Risiko itu makin kentara jika dengan pengisahan keduanya dalam satu laporan, usaha tersebut memberikan arti bahwa keduanya memiliki keserupaan secara juridis dan moral. Rezim kebenaran yang mendukung perdamaian, kedaulatan hukum dan sasaran politik rezim suksesor tidak selalu adil bagi sejarah, dan dengan demikian bisa tidak stabil dan berumur pendek. Kebenaran selalu bersifat khas untuk rezim politik tertentu. Ketegangan yang tersirat dalam transisi sejarah ini, sementara memberikan pemahaman yang bergeser tentang kekerasan di masa lalu, terlihat dalam transisi pasca-perang saudara, yang memiliki bentuk pertanggungjawaban sejarah yang khas: kesepakatan, yang dinegosiasikan setelah konflik yang menyerupai perang saudara, bergantung pada tinjauan sejarah untuk memajukan rekonsiliasi, yang merupakan tujuan politis. Penghentian konflik sering kali memerlukan komitmen bersama untuk mengadakan penyelidikan sejarah oleh kedua belah pihak, yang melibatkan representasi kekerasan dari kedua pihak. Dengan demikian, komisi pasca-perang saudara sering kali mendapat mandat untuk menyusun tinjauan sejarah yang tunggal yang mewakili kedua pihak dalam perang saudara. Terdapat kesepakatan politik untuk memberikan representasi sejarah tentang tanggung jawab bersama, meskipun peran negara tetap dominan. Tinjauan demikianlah yang paling jelas menunjukkan kaitan rezim kebenaran dengan rezim politik. Terdapat banyak ilustrasi kesepakatan hasil perundingan yang menghentikan konflik di Amerika Tengah dan Afrika. Perang saudara di El Salvador dan Guatemala berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan penyelidikan bilateral terhadap kekerasan yang dilakukan rezim dan oposisi, dengan hasil tunggal berupa laporan.56 Setelah perang saudara, tujuan konsiliatoris dari komisi kebenaran merupakan inti transisi. Dalam transisi pasca-perang saudara kontemporer, suatu laporan penyelidikan resmi yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan oposisi memberikan suatu bentuk rekonsiliasi berdasarkan sejarah. Maka, dalam laporan kebenaran El Salvador, pengisahan tentang perang saudara di negeri itu, yang disebutkan sebagai “tindakan kekerasan yang serius”, disusun secara formal dalam dua bagian setara, yang masing-masing berjudul “Kekerasan terhadap Pihak Lawan oleh Agen Negara” dan “Kekerasan terhadap Pihak Lawan oleh Frente Farabundo Marti para La Liberaciόn Nacional”. Perimbangan antara kekerasan negara dan oposisi dilakukan dengan contoh-contoh kasus yang paradigmatik. Laporan Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala merujuk masa lalu negara itu sebagai “pertikaian antar-saudara” yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara dan pemberontak.57 Dengan jumlah korban yang besar dari perang saudara di El Salvador dan Guatemala, mandat komisi kebenaran untuk mencapai rekonsiliasi bergantung terhadap penyelidikan terbatas pada kasus-kasus contoh – dari kedua belah pihak. Lihat “Guatemalan Foes Agree to Set up Rights Panel”, New York Times, 24 Juni 1994, rubrik Internasional. Guatemala’s “Memory of Silence”: Report of the Commission for Historical Clarification (Kesimpulan), 1, tersedia di http://hrdata.aaas.org/ce/report/english/conc.1.html. Lihat Report of the Truth and Reconciliation Commission (“Rangkuman dan Panduan isi”) 9-11, tersedia di http://www.truth.org.za/final/execsum.htm. Komisi Klarifikasi Sejarah dibentuk melalui Kesepakatan Oslo, 23 Juni 1997. 56 57 20 Jadi, dua jenis kekerasan, yang dilakukan negara dan oposisi, dipaparkan secara sejajar, dalam suatu jilid laporan kebenaran.58 Sejarah yang dikisahkan ini berimbang, dan merupakan suatu narasi yang diciptakan untuk mendukung kesepakatan politik. Kesepakatan serupa menjadi hukum di Afrika Selatan. Mandat komisi kebenaran di negara ini adalah untuk menyelidiki pelanggaran rezim pendahulu, sekaligus juga pelanggaran yang dilakukan aktor-aktor non negara.59 Suatu permasalahan kesetaraan moral dimunculkan oleh Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Fokus jilid kedua dari laporan ini adalah para pelaku. Sementara laporan itu dimulai dengan pemaparan tentang peran negara, tepat setelah bagian ini adalah pembicaraan tentang “gerakan pembebasan” dan peran mereka dalam pelanggaran. Kesetaraan lebih lanjut tampak dalam proses pencarian kebenaran. Para pelaku dan korban secara umum dianggap setara; para pelaku dianalogikan dengan para korban, dan dengan demikian, memiliki kedudukan yang sama. Yang bersalah maupun yang tidak sama-sama korban ... Keluarga dari mereka yang disiksa, dilukai atau mengalami trauma diberdayakan untuk menemukan kebenaran, dan para pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka. Negeri ini memulai proses panjang namun penting untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu ...60 Implikasi etis dan politis dari narasi transisional demikian diperlihatkan oleh “laporan” Hannah Arendt tentang pengadilan utama kejahatan Nazi di Israel.61 Laporan pengadilan Arendt ini berisikan sekumpulan argumen normatif, yang utamanya membahas tanggung jawab Eichmann sebagai pelaku terhadap para korbannya. Pemaparan peran birokratis Eichmann yang dibandingkan dengan peran para korbannya dalam satu laporan yang sama inilah yang dianggap mendukung klaim utama Arendt tentang “begitu biasanya” kejahatan. Risiko politisasi keadilan historis transisional digambarkan dalam laporan kebenaran transisional. Bila perundingan damai sepakat untuk bersama-sama menggabungkan penyelidikan terhadap kejahatan negara bersama dengan kejahatan pihak lainnya, pilihan komisi untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu memiliki risiko tampak sebagai versi sejarah dari “pengadilan sandiwara”. Timbul pertanyaan tentang sejauh mana kesepakatan politik sebelum terbentuknya komisi membatasi independensi dan bahkan menentukan arah penyelidikan sejarah. Representasi politik berada pada spektrum kontinuitas dan diskontinuitas, dengan implikasinya yang terkait bagi kemungkinan perubahan ke arah demokrasi. Bila kedua jenis kekerasan diselidiki oleh satu komisi, terdapat gambaran kontinuitas, bahwa pelanggaran negara bersifat relatif, bahwa aparat penindasan negara serupa saja dengan oposisi politik. Proses bersama penyelidikan dan pelaporan kekerasan dari kedua pihak ini menempatkan keduanya dalam kategori yang paralel dan memberikan perbandingan El Salvador Truth Commission Report, 6-7. Lihat Mark Deanner, “The Truth of El Mozote”, New Yorker, 6 Desember 1993, 6-7. 59 Lihat Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995 (merujuk pada sasaran “membuat gambaran selengkap mungkin ... tentang pelanggaran berat hak asasi manusia ... termasuk ... perspektif para korban dan motif serta perspektif orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran”), 801; Alex Boraine et al. (eds.), Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, CapeTown: Idasa, 1994. Lihat juga Emily H. McCarthy, “South Africa’s Amnesty Process: A Viable Route toward Truth and Reconciliation”, Michigan Journal of Race and Law 3 (musim gugur 1997): 183. 60 Azanian Peoples Organization (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa 1996 (4) SALR 671, 683-84 (CC). 61 Arendt, Eichmann in Jerusalem. 58 21 yang kontroversial: dengan menempatkan kedua macam kekerasan dalam satu dokumen, melalui penyejajaran keduanya, terciptalah representasi simetris dan bahkan anggapan bahwa kejahatan yang mereka lakukan sebanding – ekuivalen secara moral. Narasi transisional dapat distrukturkan sedemikian rupa untuk menceritakan berbagai kisah. Sebagai contoh, ada pertanyaan tentang seberapa luas analisis sejarah perlu dilakukan dalam proses penyelidikan kasus-kasus tertentu. Dengan latar belakang sejarah yang panjang, kisah yang terlihat adalah kekerasan siklik. Bila tinjauan sejarah diorganisasikan sedemikian hingga menggunakan kategori dan penilaian sejarah yang telah ada, sifat dan penyebab kekerasan menjadi tampak terlalu terdeterminasi dan tidak mengakui perubahan.62 Komisi-komisi transisional bisa juga membentuk rezim-rezim kebenaran yang transformatif secara radikal. Bila laporan kebenaran dari rezim penerus menunjukkan represi di masa lalu dalam kategori-kategori yang bersesuaian dengan “sejarah” versi rezim lama, representasi ini memajukan respon yang kritis. Pembantahan sejarah versi lama secara transformatif bergantung pada penggunaan kategori juridis yang merespon rezim kebenaran lama. Respon dan bantahan ini merupakan satu bentuk pertanggungjawaban historis. Model ini memungkinkan dengan prinsip-prinsip dokumentasi, representasi dan penguatan kebenaran dalam versi yang baru. Dengan mentransformasi kategorisasi lama, laporan kebenaran mengungkapkan sifat-sifat pelanggaran negara. Hasil yang dicapai oleh dokumentasi yang dilakukan komisi kebenaran adalah suatu versi baru sejarah yang dapat dipercaya. Dalam hal ini terdapat keserupaan antara keadilan historis dan peradilan pidana: sebagaimana halnya pengadilan memutuskan “kebenaran” dari satu pihak tentang suatu hal yang dipermasalahkan, demikian pula penyelidikan kebenaran transisional berpuncak pada keputusan serupa. Kebenaran atau Keadilan: Kebenaran sebagai Pendahulu Keadilan? Pertimbangkanlah peran narasi sejarah yang diciptakan pada masa transformasi politik. Hingga sejauh mana pengisahan kebenaran transisional merupakan bentuk keadilan? Apakah mereka merupakan pendahulu, atau alternatif terhadap keadilan? Hingga sejauh mana pertanggungjawaban sejarah merupakan sasaran dalam masa transisi, dan bukan cara untuk mencapai sasaran lain? Sejauh mana konstruksi kebenaran bersifat performatif, dan sejauh mana bersifat instrumental? Sebuah fungsi performatif utama dalam konstruksi kebenaran transisional adalah “rekonsiliasi”, yaitu dengan membawa para pelaku dan korban dalam dengar pendapat komisi, dan melalui kesaksian mereka, berpartisipasi dalam proses negara. Selain kesaksian para korban, komisi juga bergantung pada pengakuan para pelaku. Ini merupakan hal penting bila rekonsiliasi menjadi sasaran. Dengan mempertemukan para pelaku dan korban untuk membicarakan pengalaman mereka, penyelidikan komisi kebenaran merupakan dramatisasi bersama-sama tentang masa lalu. Bila korban dan pelaku menceritakan pengalaman mereka, terdapat penyembuhan dan kemungkinan perubahan diri tentang pengalaman yang sudah terjadi. Namun, meskipun proses tersebut memiliki fungsi katarsis yang penting, masih terdapat potensi konflik laten antara kebutuhan para korban dan pelaku dan kepentingan negara. Dalam berbagai transisi, para korban telah menentang undangundang amnesti untuk mengendalikan dan mendapatkan pemenuhan “hak” mereka untuk 62 Lihat Guatemala’s “Memory of Silence” (“Kesimpulan dan Saran”). 22 mendapatkan pengetahuan. Contoh utamanya adalah ibu-ibu Plaza de Mayo di Argentina dan keluarga Biko di Afrika Selatan.63 Selain potensi konflik ini, kebenaran menimbulkan konsekuensi lain. Perubahan interpretasi memberikan justifikasi untuk perubahan politik lainnya. Begitu rezim kebenaran baru ditetapkan, ia memiliki konsekuensi lebih lanjut karena ia menjadi standar untuk menentukan klaim-klaim lainnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban sejarah mengarahkan dinamika dalam transisi. Bila terdapat respon yang baru saja dikonstruksi, ia mengubah latar belakang politis dan hukum. Jadi, “kebenaran” bukanlah suatu respon yang otonom; rekonstruksi terhadap fakta-fakta sosial tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik kemasyarakatan lainnya. Bila “kebenaran” terungkap, ketika pengetahuan-pengetahuan kritis tertentu diakui secara terbuka, pengetahuan bersama ini menggerakkan respon-respon legal lainnya, seperti sanksi bagi pelaku pelanggaran, reparasi bagi para korban dan perubahan institusional. Di beberapa negara, eksplorasi terhadap masa lalu diawali dengan mandat untuk melakukan penyelidikan secara umum. Beberapa menganggap pencarian kebenaran sebagai tahap awal yang mengarah pada proses legal lainnya, seperti pengadilan, sementara ada pula anggapan bahwa penyelidikan kebenaran merupakan alternatif independen dari respon-respon lainnya. Sebagai contoh, laporan Argentina, Nunca Más, adalah tahap pertama dalam proyek negara itu untuk menyikapi masa lalunya. Sementara pada umumnya komisi kebenaran tidak mengungkapkan nama pelaku pelanggaran,64 di Argentina, bila terdapat kecurigaan, komisi menyampaikan daftar nama-nama yang ia temukan kepada pengadilan, dan kecurigaan tersebut akan mengarah pada pengadilan terhadap individu pelaku pelanggaran. Pengungkapan pelanggaran di masa lalu memiliki konsekuensi lain, yaitu pengadilan. Peran transisional penyelidikan resmi sebagai tahap pertama dalam keseluruhan respon ini serupa dengan masa biasa. Misalnya, di Kanada dan Australia, penyelidikan sejarah untuk menyelidiki peran negara-negara tersebut dalam Perang Dunia Kedua berpuncak pada pengadilan pidana. Kecuali bila penyelidikan kebenaran dikekang secara apriori, ia akan mengarah ke berbagai respon: pengadilan, sanksi lain, ganti rugi kepada korban dan perubahan struktur. Kebenaran atau keadilan? Sekali lagi, usaha penyelidikan kebenaran di beberapa negara bukanlah dianggap sebagai pendahulu, namun sebagai alternatif penghukuman.65 Dalam konteks-konteks ketika pengadilan tidak dimungkinkan atau secara politis tidak dianjurkan, proses penyelidikan sejarah disarankan sebagai alternatif terhadap pengadilan. Sebagai contoh, di Cili, El Salvador, Guatemala dan Afrika Selatan, di mana keadilan retributif tidak dijalankan, penyelidikan-penyelidikan yang dikendalikan dengan ketat, tampaknya bisa mencapai kepentingan negara untuk “menghukum” dalam bentuknya yang lain. Dalam laporan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili, kebenaran itu sendiri merupakan suatu “putusan moral”. Lihat AZAPO and Others, 1996 (4) SALR 671 (CC). Lihat “Quien está contra la Nación?” Madres de la Plaza de Mayo, januari 1985, 11. 64 Hampir semua komisi kebenaran memiliki suplemen yang bersifat rahasia, kecuali laporan komisi kebenaran Chad, yang memuat daftar nama pelaku pelanggaran beserta foto mereka. 65 Bandingkan Naomi Roht-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Human Rights Violations in International Law”, California Law Review 78 (1990), 449, dengan José Zalaquett, “Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Applicable Priciples and Political Constraints”, Hamline Law Review 13 (1990): 623. 63 23 Sering kali ada anggapan bahwa kebenaran harus dibayarkan dengan keadilan. Namun, seperti dibicarakan di muka tentang peradilan pidana, konstruksi pengetahuan publik tentang masa lalu yang penuh penindasan memiliki berbagai bentuk, sehingga pilihan antara penyelidikan pidana atau penyelidikan sejarah tidak identik dengan pilihan antara keadilan atau kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah “kebenaran” yang bagaimana? Ciri utama rezim kebenaran dalam masa transisi berkaitan dengan sejauh mana masyarakat yang baru dapat mentolerir berbagai representasi “kebenaran”. Bila transisi bisa dicapai dengan janji adanya rekonsiliasi di masa depan antara berbagai elemen masyarakat yang terbagi-bagi, terdapat usaha untuk mencapai pandangan yang serupa tentang sejarah. Konsensus sejarah terkait erat dengan pembangunan konsensus politik. Dengan demikian, sering kali terdapat usaha untuk membatasi versi-versi lain dari sejarah, dan diberikanlah insentif bagi para korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam proses sejarah resmi. Pengampunan dan amnesti yang ditawarkan dan dijanjikan digunakan untuk mencegah timbulnya versi lain dari sejarah yang bisa melemahkan versi sejarah yang resmi, yang tampak dalam penyelidikan kontemporer di Afrika Selatan. Batasan yang diterapkan untuk mencegah munculnya versi-versi lain dari sejarah merupakan semacam “aturan pengendali”.66 Bentukbentuk aturan pengendali lainnya tampak dalam konstitusi transisional, yang akan dibicarakan di bagian lain bab ini. Kebenaran tidak selalu sama dengan keadilan; namun ia juga tidak selalu terpisah. Pemahaman yang lebih baik adalah yang menganggap bahwa kebenaran adalah suatu elemen dari keadilan. Dengan demikian terdapat kedekatan antara pertanggungjawaban sejarah dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban transisional lainnya, yang semuanya membangun pengetahuan bersama tentang masa lalu. Sejarah transisional memajukan tujuan epistemik dan ekspresif yang diasosiasikan dengan sanksi pidana. Kedekatan lain antara pertanggungjawaban historis dan pidana adalah pembebanan tanggung jawab individual untuk pelanggaranpelanggaran di masa lalu. Hal ini tampak jelas dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca-apartheid, di mana pengakuan sejarah dijadikan syarat untuk pemberian amnesti individual, kasus demi kasus. Sebagaimana dalam skema pidana, pengakuan individual ini memiliki unsur-unsur penghukuman, karena penyelidikan dilakukan untuk menetapkan kesalahan individu, dengan temuannya kemudian diungkapkan dalam masyarakat dalam proses ritual yang formal. Pengungkapan pelanggaran para pelaku itu dengan sendirinya merupakan bentuk penghukuman yang tidak formal, “memalukan” dan memberikan sanksi sosial bagi para pelakunya. Bentuk sanksi ini memiliki risiko pengutukan yang tidak terbatas, dan pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan hukum.67 Satu kaitan lain antara keadilan historis dan bentuk-bentuk keadilan lainnya adalah pengungkapan kejahatan di masa lalu dapat memberikan suatu macam reparasi atau pemulihan bagi para korban, juga menarik garis pembatas antara rezim. Pengungkapan kisah para korban dapat “meluruskan” sejarah, seperti tuduhan kejahatan politik di masa sebelumnya, seperti di Amerika Latin, di mana banyak korban yang dihilangkan dituduh melakukan subversi. Rehabilitasi reputasi yang serupa memainkan peranan penting di Eropa Timur dan Rusia. Rehabilitasi tahanan politik dari masa Stalin, yang berjumlah ribuan, masih merupakan kerja Lihat Stephen Holmes, Passions and Constraint, Chicago: University of Chicago Press, 1995 (membicarakan peran konstitutif “aturan pengendali”). 67 Untuk analisis kritis tentang tindakan mempermalukan, lihat James Whitman, “What is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?” Yale Law Journal 107 (1998): 1055. 66 24 penting dari organisasi hak asasi manusia di sana, yang terutama dikerjakan oleh Memorial, organisasi yang dibentuk pada akhir dekade 1980-an untuk mengungkapkan penindasan politik. Pelurusan sejarah bagi para korban dilakukan dengan berbagai cara, dengan mengalahkan tuduhan di pengadilan, mengesahkan perundang-undangan, memberikan permintaan maaf dalam laporan kebenaran dan menerbitkan bantahan terhadap versi sejarah rezim lama. Di sini terlihat tujuan korektif dari keadilan historis transisional. Tujuan kebenaran dalam hal ini adalah mengembalikan harga diri para korban, termasuk mengembalikan perdamaian dan rekonsiliasi. Nilai penting keadilan historis menunjukkan kedekatan dengan bentuk-bentuk keadilan transisional lainnya dalam liberalisasi, dengan tujuannya yang korektif, yang tampak dalam banyaknya saran-saran yang diberikan dalam laporan kebenaran, yang bersifat struktural. Sebagai contoh, ketika komisi kebenaran El Salvador melaporkan bahwa tanggung jawab untuk pelanggaran berat hak asasi manusia berada pada komando tertinggi militer, ia menyarankan untuk mengadakan “pembersihan” pada perwira-perwira tinggi dalam struktur tersebut.68 Ketika pemerintahan represif di Amerika Latin dianggap disebabkan karena tidak ada badan peradilan yang independen, sebagaimana dapat dibaca dari berbagai laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di daerah itu, maka laporan-laporan tersebut sering kali menyarankan diperkuatnya badan-badan peradilan; demikian pula perubahan mendalam tentang budaya hukum, terutama yang menyangkut hak asasi manusia.69 Usaha pertanggungjawaban transisional ini sering kali menjadi institusi permanen, seperti komisi kebenaran Uganda, yang kemudian berubah menjadi badan hak asasi manusia permanen untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh rezim baru yang dipilih secara terbuka.70 Hal serupa terjadi di Cili, di mana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kemudian menjadi Badan Pemulihan dan Rekonsiliasi Nasional Cili, yang juga menyikapi kasus-kasus baru yang muncul belakangan.71 Akhirnya, penyebarluasan laporan kebenaran dalam masyarakat baru pasca represi dilakukan sebagai usaha untuk mengubah opini publik tentang tirani negara. Laporan kebenaran biasanya mengungkapkan bahwa di masa lalu masyarakat luas menerima teror negara begitu saja. Penerimaan masyarakat, terutama di tingkat elite, mengungkapkan bahwa pelanggaran hak merupakan hal yang bisa diterima sebagai ganti kendali yang lebih kuat terhadap oposisi; dan sikap inilah antara lain yang memungkinkan kuatnya penindasan militer di suatu wilayah.72 Jika penghukuman menunjukkan tindakan-tindakan apa saja yang tidak akan ditolerir oleh masyarakat, banyak masyarakat pasca-rezim militer yang belum mencapai konsensus tentang apa yang tidak bisa diterima, dan lebih spesifiknya, bahwa kediktatoran merupakan tindakan kriminal. Interpretasi kritis laporan kebenaran terhadap rezim pendahulu, seperti juga dilakukan oleh proses pengadilan, bisa memecahkan kebekuan yang menjadi ciri pemerintahan represif di masa lalu. Pada akhirnya, toleransi masyarakat terhadap penindasan oleh negara akan berkurang. Laporan Komisi Kebenaran El Salvador, 176. Lihat misalnya Laporan CONADEP, 386-425. Lihat juga Laporan Rettig, 117-29. 70 Lihat Human Rights Watch, Commission of Inquiry Investigates Causes of Abuses in Uganda, New York: Human Rights Watch, 1989. 71 Lihat Informe Sobre Calificación de Victimas de Violaciónes de Derechos Humanos y de la Violencia Politica, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (Chile, 1996). 72 Lihat misalnya Jacobo Timerman, Prisoner without a Name, Cell without a Number, New York: Knopf, 1981. 68 69 25 Dengan peran komisi kebenaran dan laporan-laporannya dalam mengubah sikap masyarakat terhadap represi oleh negara, bagaimana transformasi ini memungkinkan keadilan historis dalam arti pertanggungjawaban? Bagaimana narasi laporan resmi itu membangun perasaan pertanggungjawaban historis? Dalam hal apa kebenaran ini bisa dianggap sebagai keadilan historis? Meskipun laporan kebenaran transisional pada umumnya mengklaim untuk tidak berperan sebagai “pengadilan”,73 klaim demikian sebenarnya merujuk pada arti sempit dari pengadilan. Dari bentuk penyelidikan dan pelaporan kebenaran, ritual formal dengan berbagai tuduhannya yang mendetail, penyelidikan kebenaran memiliki keserupaan dengan proses pidana. Laporan-laporan tersebut dapat dikatakan merupakan bentuk keputusan pengadilan, karena tinjauannya tentang sejarah menggunakan bahasa hukum dalam merespon pelanggaran hak individual. Tinjauan sejarah ini ditulis dalam bahasa hukum, dengan peristilahan status, hak, kesalahan, kewajiban, klaim dan perizinan. Bila para pelaku tidak dituding secara individu, seperti biasanya dilakukan dalam laporan kebenaran, subjek keputusan tersebut adalah masayarakat luas. Model peninjauan ini lebih kemprehensif daripada model peradilan pidana. Paling tidak, laporan kebenaran demikian memungkinkan perasaan keadilan historis secara luas, kalau bukan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku, mengembalikan harga diri dan pemulihan bagi para korban. Dalam peradilan pidana, tinjauan ini, seperti proses ajudikasi, bersifat kasus demi kasus. Sementara, penyelidikan administratif bisa memfokuskan sejarah secara lebih luas, sehingga memahami konteks luas peninggalan sejarah, struktur sosial dan politik suatu negara, yang semuanya terkait dengan masalah pertanggungjawaban terhadap kesalahan. Dalam penyelidikan sejarah yang lebih luas, para pelaku dan korban dikaitkan lagi dalam penyelidikan terhadap kebijakan penindasan oleh negara. Proses komisi kebenaran menggambarkan respon sejarah terhadap pemerintahan represif, juga kaitan antara rezim politik dan sejarah. Dengan memberikan respon yang kritis terhadap representasi sejarah, hukum dan politik dari rezim masa lalu tentang penindasan di masa lalu, laporan kebenaran resmi merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam masa transisi dan merespon klaim bahwa semua hal tersebut bersifat politis. Dalam proses komisi kebenaran, kebenaran politik dikonstruksikan secara instan, menunjukkan bagaimana perubahan rezim kebenaran berkaitan dengan perubahan rezim politik. Sifat khas bentukbentuk dan proses-proses dalam sejarah transisi menunjukan sifat instrumental dari responrespon tersebut, yang sering kali dipolitisasi dalam arti bahwa kebenaran yang relevan adalah pengetahuan umum yang diperlukan untuk mendorong transformasi masyarakat. Oleh respon transisional yang penting ini, diciptakanlah suatu “kebenaran” yang secara terbuka dan eksplisit merupakan konstruksi politik, yang mengarahkan transisi. Kita kembali ke pertanyaan di awal bab ini: apa sifat dan peran sejarah dalam transisi? Transisi menunjukkan kerangka sosial penyelidikan sejarah. Meskipun pada umumnya dikatakan bahwa kerangka sosial dan politik pada suatu masa mempengaruhi konstruksi ingatan kolektif,74 kaitan pada masa biasa ini tidak terdapat dalam masa transisi. Pembangunan ingatan kolektif pada masa transformasi radikal dicirikan oleh konteks kerangka transisional yang relevan. Proses pencarian kebenaran resmi, seperti komisi sejarah, secara eksplisit dirancang untuk mencapai masa depan yang lebih demokratis. Di sinilah tampak tujuan Lihat misalnya Nunca Más, pembukaan. Lihat Maurice Halbwachs, On Collective Memory (ed.: Lewis A. Coser), Chicago: University of chicago Press, 1992. 73 74 26 transformatif sejarah, suatu peran politis yang mengarah ke depan, dalam rekonsiliasi dan liberalisasi nasional. Kebenaran yang tercipta adalah tentang masa lalu “yang dapat diterima” untuk masa depan yang lebih baik. Sejarah transisional memiliki peran ganda untuk mengecilkan sekaligus menunjukkan kembali hal-hal yang direpresi di masa lalu. Yang tercipta adalah narasi liberalisasi yang performatif, yang dalam konteks politik suatu negara dapat membantu proses liberalisasi. Keadilan Historis setelah Totalitarianisme Tiang utama sistem totaliter masa kini adalah keberadaan satu sumber utama semua kebenaran dan semua kekuasaan, suatu “pemikiran sejarah” yang terinstitusionalisasi. .... Dalam masa pasca-totaliter, kebenaran dalam arti seluas-luasnya memiliki nilai yang amat penting, yang tidak dikenal dalam konteks-konteks lainnya. Dalam sistem ini, kebenaran memiliki peran yang jauh lebih besar (dan sangat berbeda) sebagai faktor kekuasaan, atau sebagai kekuatan politik yang signifikan. Bagaimana kekuatan kebenaran bekerja? Bagaimana kebenaran sebagai faktor kekuasaan bekerja? Bagaimana kekuatannya – sebagai kekuatan – dapat terlaksana? (Václav Havel, Open Letters: Selected Writings, 1965-1990) Hegel menyatakan bahwa semua fakta dan tokoh besar dalam sejarah muncul dua kali. Ia lupa menambahkan: yang pertama kali sebagai tragedi, yang kedua sebagai lelucon yang tidak lucu. (Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte) Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa (Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting) “Hidup dalam kebenaran” merupakan slogan banyak kelompok penentang rezim Komunis.75 Namun, setelah perubahan politik, apa arti sebenarnya dari “hidup dalam kebenaran?” Bagaimana bergeser dari “hidup dalam kebohongan” ke masyarakat yang terbuka? Kediktatoran tradisional, seperti militer di Amerika Latin, cenderung menggunakan kekuasaannya dengan kerahasiaan, penghilangan dan impunitas, untuk memerintah di luar sejarah. Bila hal ini merupakan kaitan pengetahuan dan kekuasaan dalam masa rezim pendahulu, respon transisionalnya adalah untuk secara terbuka mengkonstruksikan tinjauan sejarah kolektif tentang masa yang dipermasalahkan. Sebaliknya, setelah komunisme, penyelidikan kebenaran resmi tidak menjadi pilihan respon yang umum. Respon ini tampaknya tidak tepat dalam konteks transisi dari pemerintahan totaliter, di mana sejarah resmi negara memainkan peran integral dalam represi. Sejarah progresif menurut ideologi Marxis merupakan usaha untuk merasionalkan negara totaliter. Di seberang Tembok Berlin, simbol penindasan totaliter adalah aparat keamanan negara dan metode pengawasannya. Yang mencirikan totalitarianisme adalah totalitas kekuasaan negara, termasuk usaha untuk Václav Havel, “The Power of the Powerless”, dalam Open Letters: Selected Writings, 1965-1990 (ed.: Paul Wilson), New York: Random House, Vintage Books, 1992, 147-48. 75 27 menguasai budaya dan sejarah sepenuhnya. Usaha ini mencakup penggunaan sejarah negara untuk tujuan politis secara terbuka.76 Suatu pertanyaan yang sukar adalah, apa yang perlu dilakukan dengan sejarah negara yang diciptakan oleh rezim lama ini? Misalkan kata arsip, yang memiliki akar arche, yang berarti “awal” sekaligus “pemerintahan”. Dalam masa transisi, kaitan antara pemerintahan dan awal normatifnya menjadi tampak amat jelas.77 Sementara setelah kediktatoran, terdapat konsensus tentang pentingnya pengungkapan sejarah masa lalu, dalam transisi pasca-komunis tidak ada konsensus demikian. Dengan runtuhnya rezim, timbul pertanyaan tentang apa yang perlu dilakukan dengan sejarah versi lama ini. Setelah komunisme berakhir, anggapan bahwa perlu dilakukan penyusunan sejarah resmi untuk keberhasilan transisi tampak salah sama sekali. Setelah pemerintahan totaliter yang menindas, apa arti kebenaran transisional yang resmi? Karena peninggalan penggunaan politis sejarah resmi oleh rezim totaliter, transisi dari komunisme biasanya tidak melakukan proses peninjauan sejarah tentang penindasan di masa lalu. Pergeseran dari pemerintahan totaliter tidak diwarnai dengan penyelidikan sejarah dalam skala besar yang dikaitkan dengan pergeseran politik dari kediktatoran militer. Keadilan historis transisional memiliki arti lain yang spesifik bagi rezim-rezim pengganti komunisme. Bila penindasan di bawah kediktatoran di Amerika Latin terjadi dalam bentuk penghilangan dan ketidakpastian, di bawah pemerintahan komunis, penindasan memiliki bentuk yang lebih material dalam totalitas kendali negara terhadap konstruksi peristiwa-peristiwa sejarah. Peninggalan ini mempengaruhi respon sejarah dalam transisi. Dengan adanya dokumentasi “sejarah” oleh rezim lama yang merasuk ke semua unsur kehidupan masyarakat, seperti juga kendali terhadap semua bidang lainnya, apa arti kebebasan? Dalam arti apa mengetahui sejarah dapat membebaskan? Sejarah siapa? Pengetahuan siapa? Sementara tidak banyak keinginan untuk menciptakan sejarah resmi tentang masa pemerintahan komunis yang berkepanjangan, respon transisional diarahkan untuk mengungkapkan kebenaran tentang momen-momen politik yang kritis dalam represi di masa lalu dan mendapatkan akses pada sejarah yang semula ditutup-tutupi. Penyelidikan sejarah pasca-totaliter berfokus untuk menjelaskan penerapan pemerintahan yang menindas. Pengetahuan ini saja bersifat anti-totaliter: seperti juga pada keadilan suksesor pascapemerintahan militer, penyelidikan pasca-komunis ini ditujukan untuk melawan representasi lama tentang momen-momen politik yang penting. Arti keadilan historis transisional didefinisikan dalam konteks sejarah negara yang lama. Dengan merespon representasi lama ini, tinjauan demikian merupakan bentuk tinjauan yang kritis. Pertanggungjawaban sejarah dikembangkan dari momen-momen politis penting dari suatu negara yang menarik garis batas antara kebebasan dan penindasan. Di Rusia, pembukaan arisp KGB dan Partai Komunis adalah hal yang amat politis. Ini berperan penting dalam pengujian terhadap konstitusionalitas Partai Komunis, dengan akses pada arsip-arsip yang memungkinkan terungkapnya tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan partai Lihat Karl Marx dan Friedrich Engels, “Manifesto of the Communist Party”, dalam The Marx-Engels Reader, edisi kedua (ed:. Robert T. Tucker), New York: W.W. Norton, 1978. 77 Webster’s New Collegiate Dictionary, entri “archive”. Untuk pembahasan eksegesis lebih lanjut tentang topik ini, lihat Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression (terjemahan Eric Prenaowitz), Chicago: University of Chicago Press, 1996. 76 28 tersebut selama bertahun-tahun.78 Politisasi arsip-arsip di Rusia ini dapat pula dilihat dengan tidak adanya perundang-undangan; akses didapatkan berkat adanya izin dengan keputusan presiden yang mengalihkan isi arsip-arsip dari Partai dan KGB kepada negara.79 Bagi negaranegara Eropa Timur yang sedang mengalami transisi dari pemerintahan totaliter, pertanyaan utama dalam keadilan historis adalah “penindasan siapa?” Masa totaliter ini bisa dianggap sebagai masa pendudukan oleh kekuatan asing, atau penindasan dari dalam. Pertanyaan sejarah ini memiliki dampak politis dan hukum yang penting. Di seluruh wilayah ini, terdapat usaha untuk merekonstruksi celah-celah sejarah yang penting dan titik-titik balik politik yang penting yang berkaitan dengan penerapan pemerintahan komunis yang represif: bagi Hungaria, represi terhadap pemberontakan 1956, bagi Cekoslowakia, 1968 dan 1989, dan bagi Polandia, 1981. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk menerangi lembar-lembar hitam dalam perang dingin. Di bekas Cekoslowakia, paling tidak terdapat dua momen penting: yang pertama adalah kekerasan terhadap pemberontakan 1968 di Praha. Kebenaran sejarah selengkapnya tentang invasi ini menjadi subjek Komisi Penyelidikan Peristiwa-Peristiwa 1967-1970 dari pemerintahan Cekoslowakia, yang dimungkinkan dengan runtuhnya kendali Soviet di wilayah tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan dibukanya arsip-arsip negara-negara yang terlibat dalam invasi Agustus 1968 itu. Komisi yang dibentuk pada tahun 1989 ini menyelesaikan tugasnya pada tahun 1992, dan mengalihkan dokumentasinya pada Institut Sejarah Modern. Momen kedua adalah revolusi pada tahun 1989. Suatu penyelidikan yang terkait dengan penyelidikan di atas dilakukan terhadap peristiwa 17 November 1989 dan represi pemerintah terhadapnya. Sebuah penyelidikan resmi oleh “Komisi 17 November” yang dibentuk parlemen, dilakukan dengan puncaknya berupa penyiaran sidang Dewan Federal untuk menyampaikan laporan komisi tersebut pada tanggal 22 Maret 1991. Pemaparan yang terbuka dan amat politis ini mengarah pada “lustrasi”80 dan menunjukkan penggunaan pengetahuan tentang masa lalu sebagai cara pembersihan, suatu kebijakan yang akan dibahas dalam bab 5. Di Warsawa, harapan untuk adanya perubahan politik muncul dan dihancurkan pada tanggal 13 Desember 1981. Pada hari itu, pimpinan politik Polandia masa itu, Jenderal Wojciech Jaruzelski menerapkan hukum perang untuk menghancurkan gerakan oposisi Solidaritas. Setelah tahun 1989, momen sejarah itu menjadi subjek Komisi Pertanggungjawaban Konstitusional yang dibentuk oleh Sejm (parlemen).81 Sementara Polandia tidak melakukan kebijakan retribusi (penghukuman), penyelidikan parlementer terhadap peristiwa Desember 1981 ini merupakan satu dari sedikit tindakan yang memandang ke belakang yang dilakukan. Pertanyaan penting yang mendorong penyelidikan itu adalah: Siapa yang bertanggung jawab atas masa represif yang dikenal sebagai “invasi internal” Polandia ini? “Kita” atau “mereka”? Sejauh mana represi di negara itu merupakan tanggung jawab internal dan eksternal? Baik eksternal atau tidak, sejauh mana tindakan kekerasan Untuk tinjauan tentang hal ini, lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30 November 1992, 104-21. 79 Keputusan No. 82, 83, 24-08 (1991). Tentang arsip Rusia, lihat Vera Tolz, “Access to KGB and CPSU Archives in Rusia, Politics” Vol. 1 No. 16 (17 April 1977); N. Ohitin dan A. Roginsky, “Remarks on Recent Status of Archives in Rusia” dalam Truth and Justice: The Delicate Balance, The Inst. For Constitutional and Legislative Policy C.E.U. 19930. 80 Lihat Jan Obrman, Laying the Ghosts of the Past (laporan tentang Eropa Timur, No. 24, 14 juni 1991). 81 Lihat Tadeusz Olszaski, “Communism’s Last Rulers: Fury and Fate”, Warsaw Voice, 18 November 1992. 78 29 terhadap Solidaritas yang dilakukan selama 19 bulan itu dapat dijustifikasi untuk mencegah invasi Soviet? Apakah tindakan tersebut diperlukan? Bahkan tanpa penyelidikan pidana lebih lanjut, rezim Jaruzelski minimal harus memberikan pertanggungjawaban historis. Tanggal 31 Oktober 1956 adalah titik balik bagi Hungaria, hari terjadinya penindasan terhadap pemberontakan rakyat yang melawan kediktatoran. Yang mendorong penyelidikan transisional adalah pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap penindasan pada tahun tersebut. Pemerintahan pada masa itu atau Soviet? Kita atau mereka? harapan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang independen tentang masa itu didorong oleh adanya akses terhadap arsip-arsip Soviet. Namun pada akhirnya, akses tersebut tidak memberikan banyak penjelasan dan tidak menjawab pertanyaan pertanggungjawaban historis, seperti apakah peristiwa tahun 1956 tersebut merupakan undangan dari pemerintah terhadap pasukan pendudukan, atau invasi berskala penuh?82 Ada cukup bukti yang menunjukkan kerja sama dan kolusi antara Soviet dan aparat partai komunis setempat dalam represi pada tahun 1956. Laporan-laporan yang ada menunjukkan bahwa para pemimpin Partai Pekerja Sosialis Hungaria yang beraliran komunis dan para komandan militer bertanggung-jawab terhadap tewasnya ribuan orang dalam pemberontakan itu.83 Meskipun penyelidikan terhadap peristiwa itu dimulai dengan penyelidikan tentang pasukan pendudukan asing (“mereka”), berdasar pada konsep tanggung jawab yang eksternal, penyelidikan tersebut kemudian mengarah pada konsep tanggung jawab yang lebih internal – mengarah pada pertanyaan: Siapa “kita”? Penyelidikan sejarah ini akan mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang telah dibicarakan pada bab 2 buku ini. Di Jerman-bersatu, seperti di negara-negara lain di wilayah itu, penyelidikan sejarah dimulai dengan permasalahan tanggung jawab kolektif nasional. Di negara ini dilakukan penyelidikan sejarah yang lebih luas daripada negara-negara lainnya di wilayah yang sama. Komisi Parlementer Eppelman, yang dinamakan sesuai ketuanya, seorang oposan Jerman Timur, mendapatkan mandat yang jauh lebih luas untuk menyelidiki tidak hanya tanggung jawab terhadap pendudukan namun juga alasan lebih luas terjadinya penindasan.84 Komisi tersebut ditugaskan untuk menyelidiki dukungan rakyat terhadap rezim Partai Persatuan Sosialis (SED), bahkan juga meninjau peran Ostpolitik – kebijakan Jerman Barat yang akomodasionis – dalam mendukung kediktatoran di Jerman Timur.85 Fokus penyelidikan ini terletak pada tanggung jawab sejarah secara luas, dan seiring jalannya penyelidikan, dilakukan penyelidikan yang spesifik terhadap kolaborator dan perlawanan. Baik Komisi 17 November Cekoslowakia maupun penyelidikan 1956 di Hungaria merangsang adanya penyelidikan Jane Perlez, “Hungarian Arrests Set Off Debate: Should ’56 Oppressors Be Punished?” New York Times, 3 April 1994, rubrik Internasional, A14. 83 Lihat “Almost 1,000 Killed in Hungarian Uprising: Fact-finding Committee”, Agence France Presse, 22 November 1993, tersedia di Lexis, News Library. Jumlah yang didokumentasikan secara resmi jauh lebih kecil daripada yang dihilangkan – mungkin ribuan. Lihat Julius Strauss, “Hunary Uprising Killers May Be Tried”, Daily Telegraph, (Budapest), 2 Desember 1993; “Almost 1,000 Victims in ’56 Mass Shootings”, MTI Hungarian News Agency, 22 November 1993, tersedia di Lexis, News Library. 84 Pada tanggal 13 Mei 1992, parlemen Jerman memberikan mandat kepada Komisi Eppelmann “untuk menyelidiki struktur, strategi dan instrumen kediktatoran komunis, masalah pertanggungjawaban untuk pelanggaran hak asasi manusia dan hak kemasyarakatan”. Lihat Stephen Kinzer, “German Panel to Scrutinize East’s Rule and Repression”, New York times, 30 Maret 1992, rubrik Internasional, A7. 85 Lihat Timothy Garton Ash, In Europe’s Name: German and the Divided Continent, New York: Random House, 1993. 82 30 pidana,86 dan berakhir dengan pembersihan administratif berskala besar dari jabatan politik.87 Kebenaran tentang apa yang terjadi di negara-negara tersebut berakhir pada ujian (atau pengadilan) terhadap kesetiaan politik – suatu hal yang bisa dianggap sebagai kebenaran para warga negara. Kontinuitas dalam respon sejarah dan administratif dalam masa transisi di wilayah ini menunjukkan bahwa pengundang-undangan aturan yang kritis merupakan rekonstruksi kebenaran dan menunjukkan pengetahuan kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik dan rekonstruksi hal-hal yang bersifat politis. Keadilan Historis dalam Bayang-Bayang Komunisme Siapa yang mengendalikan masa lalu mengendalikan masa depan; siapa yang mengendalikan masa kini mengendalikan masa lalu. (George Orwell, Nineteen Eighty-Four) Sejauh mana arsip-arsip yang disusun dalam masa pemerintahan represif dapat diandalkan dalam masa transisi? Dapatkah arsip-arsip itu diandalkan sebagaimana terjadi pada pergeseran administratif biasa dalam sistem demokrasi yang berjalan baik? Arsip merujuk pada catatan pemerintah dan tempat penyimpanannya – kedudukan penguasa. Dalam transisi dari pemerintahan totaliter, pengendalian terhadap sejarah negara menjadi sangat terkait dengan pengendalian terhadap kekuasaan politik. Pada masa pemerintahan totaliter, kebenaran terletak dalam konteks pengendalian ideologis yang dipaksakan. Dalam konteks ini, apa arti transformasi normatif? Inilah pertanyaan penting tentang apa yang perlu dilakukan terhadap arsip lama di wilayah ini. Pertanyaan ini amat terkait dengan politik masa transisi: rahasiarahasia masa lalu politis tidak bisa dilepaskan dari pengendalian masa depan politik; penyelidikan sejarah memberikan jalan bagi politik pengungkapan. Bagaimana cara menyelesaikan dilema peninggalan sejarah totaliter? Tindakan yang paling radikal adalah dengan memusnahkan arsip-arsip tersebut, suatu auto-da-fé.88 Pemusnahan arsip-arsip tersebut berarti menarik garis tegas yang memisahkan kedua rezim. Sejarah bisa dimulai lagi. Memusnahkan arsip-arsip tersebut bisa dijustifikasi dengan alasan bahwa arsip-arsip tersebut tidak dapat diandalkan dan kemungkinan berisikan kebohongan. Melindungi arsip-arsip lama memberikan kepada rezim-rezim selanjutnya kekuasaan luar biasa untuk menghancurkan reputasi individual, sehingga mempertahankan peninggalan totaliter. Sementara, memusnahkan arsip tampaknya akan menjamin agar sejarah tidak berulang. Lihat “Czechoslovakia: Former Top Police Officials Jailed”, Reuters, 30 Oktober 1992, Perlez, “Hungarian Arrests Set Off Debate”; “Former Government Officials Sentenced to Prison Terms”, CTK National News Wire, 30 Oktober 1992, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK. 87 Tentang Republik Ceko, lihat Helsinki Watch Report, Czechoslovakia: ‘Decommunization’ Measures Violate Freedom of Expression and Due Process Standards, New York: Human Rights Watch, 1992. 88 Lihat John Elster, “Political Justice and Transition to the Rule of Law in East-Central Europe” (dipresentasikan pada konferensi yang disponsori University of Chicago, Center for Constitutionalism in Eastern and Central Europe, tidak diterbitkan, Praha, 13-15 Desember 1991). Untuk diskusi tentang perdebatan di wilayah ini, lihat “Truth and Justice, The Delicate Balance: The Documentation of Prior Regimes and Individual Rights”, Kertas Kerja No. 1 (Central European University, Institute of Constitutional and Legislative Policy: Lokakarya di Budapest tentang masalah arsip, 1993). 86 31 Namun, pemusnahan arsip tampaknya terlalu radikal. Bagaimana jika pemusnahan arsip tidak dengan sendirinya meredakan kecurigaan tentang kolaborasi di masa lalu? Kecurigaan ini bisa tetap bertahan, didorong oleh sumber-sumber lainnya. Suatu konsekuensi yang lebih signifikan dari pemusnahan arsip adalah hilangnya catatan dari suatau masa yang panjang dalam sejarah suatu bangsa. Pada umumnya, pergantian pemerintahan dalam negara demokrasi mengasumsikan suksesi kearsipan,89 karena arsip negara – seperti milik negara yang lainnya – merupakan elemen identitas nasional. Analogi dengan negara-negara demokrasi yang sudah mapan mempersulit kontinuitas pengarsipan dan pengungkapan arsiparsip lama. Bahkan, kontinuitas demikian tampaknya ciri dari sistem yang menaati kedaulatan hukum. Namun apakah analogi tersebut tepat? Pertimbangan lain dari kedaulatan hukum menunjukkan diskontinuitas dan meninggalkan arsip-arsip lama. Pertimbangkanlah masalah etika bila sebuah rezim baru masih bergantung pada informasi yang didapatkan secara paksa dan rahasia, dengan invasi terhadap privasi atau malah lebih buruk lagi, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Di negara-negara demokratis yang sudah mapan, terdapat batasan terhadap pengumpulan informasi oleh pemerintah, yang antara lain terkait pada perlindungan reputasi dan hak-hak harga diri individual. Di negara liberal, tidak ada tempat bagi arsip seperti yang diciptakan oleh negara totaliter. Apakah sebaiknya pelanggaran oleh rezim pendahulu dipermasalahkan oleh rezim penggantinya? Tentu saja, hal ini kurang menjadi masalah bagi rezim pengganti. Namun, bila usaha pencarian fakta dilakukan di bawah masa rezim represif yang lama, dengan bergantung pada catatan milik rezim lama, pergeseran dari rezim lama ke rezim pengganti ini seakan-akan sama dengan pergantian administrasi dalam kedaulatan hukum yang kontinu. Ketergantungan pada arsip-arsip milik rezim lama menyulitkan pemantapan pemerintahan liberal. Namun, pada saat yang sama, karena masalah pengarsipan ini mengancam legitimasi rezim baru, pengungkapan arsip-arsip rezim lama memberikan lambang keterbukaan dalam masyarakat. Setengah abad represi oleh pasukan keamanan negara menuntut adanya keterbukaan sebagai jawaban. Alternatif terhadap hal ini adalah “komisi kebenaran” seperti di Amerika Latin, yang akan mengambil alih kontrol terhadap arsip-arsip yang ada. Namun, setelah pemerintahan Komunis, komisi kebenaran tidak menjadi pilihan di wilayah ini. Berbagai respon transisional ini tidak dapat dijelaskan oleh perspektif realis yang umum, karena berbagai respon negara ini tidak dapat dihitung dengan perimbangan kekuasaan yang sederhana. Pertanyaan tentang apakah terdapat penyelidikan terbuka sukar untuk dijelaskan dalam kerangka pemahaman umum kekuasaan politik. Pada masa transisi, pengetahuan dan kekuasaan sangatlah terkait, saling tersusun dan menyusun satu sama lain. Tindakan-tindakan bekas blok komunis yang berbeda dari tindakan negara-negara lain yang juga mengalami transisi akan dapat dijelaskan dengan melihat arti sosial partai, ideologi, dan penguasa sejarah dan kebenaran di komunitas yang bersangkutan. Konstruksi sejarah transisional dibentuk oleh konteks peninggalan sejarah dan politik di suatu wilayah. Hal sebaliknya juga terjadi, konteks politik dan budaya yang baru juga akan mempengaruhi pilihan fakta-fakta untuk dimuat dalam sejarah, selain bentuk proses penciptaan kebenaran. Negara-negara bekas blok Komunis berusaha keras untuk menyikapi peninggalan arsip-arsip masa lalunya. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan arsip-arsip tersebut menimbulkan perdebatan publik, terutama di negara-negara yang aparat keamanannya Lihat Lung-Chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law, New Haven: Yale University Press, 1989, 428-29. 89 32 paling represif. Hal ini sekali lagi menunjukkan bagaimana peninggalan masa lalu masih dapat mempengaruhi respon transisional. Jerman-bersatu dan bekas Cekoslowakia, misalnya, menggunakan berbagai pendekatan untuk menyikapi peninggalan negara represif dari masa lalu. Masing-masing negara tersebut bereksperimen dengan berbagai tingkat kebebasan dan akses terhadap arsip dari masa pemerintahan yang lalu. Pada akhirnya, dicapai kesimpulan yang merupakan kompromi, bukan pemusnahan arsip-arsip tersebut maupun akses sepenuhnya. Di balik Tembok Berlin, tidak ada simbol penindasan Komunis yang lebih jelas daripada tumpukan tinggi arsip-arsip polisi Jerman Timur (“Stasi”). Selama 40 tahun, negara melalui kementerian keamanan dan dengan dukungan Partai Komunis mengumpulkan dokumentasi tentang warganya sendiri. Jumlahnya saja sudah luar biasa: dari 18 juta warga negara, lebih dari sepertiganya diawasi oleh negara.90 Dikatakan bahwa ada “enam juta” arsip, angka yang sama dengan jumlah korban Holocaust, yang menunjukkan analogi sejarah dengan penindasan masa Perang Dunia Kedua dan mendukung argumen bahwa pada saat ini, Jerman akan “mengambil tindakan” terhadap masa lalunya.91 Dengan perubahan politik, timbul pertanyaan tentang apa yang dilakukan dengan arsip-arsip negara. Jika represi dilakukan dengan kerahasiaan, keadilan dicapai dengan mengungkapkan kebenaran. Sejak awal reunifikasi Jerman, terdapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mengungkapkan arsip-arsip ini. Maka, disahkanlah Undang-Undang tentang Arsip Dinas Keamanan Negara bekas Republik Demokratik Jerman (UU Arsip Stasi) untuk “memberikan kepada warga negara individual kemungkinan akses terhadap data pribadi yang disimpan yang menyangkut dirinya, sehingga ia bisa mengetahui apa pengaruh dinas keamanan negara terhadap dirinya”.92 Namun, seperti kemudian menjadi jelas bahkan bagi korban penindasan di masa lalu, kebebasan informasi tidak selalu merupakan hal yang baik. Pengungkapan arsip seseorang bisa berarti penemuan bahwa ia telah dimata-matai oleh anggota keluarga atau teman, yang merusakkan hubungan karier, persahabatan bahkan pernikahan.93 Terlebih lagi, sejak awalnya, pengungkapan arsip Stasi tidaklah mudah, dan menunjukkan bahwa hal ini memiliki dua sisi. Meskipun undang-undang ini menurut namanya ditujukan untuk mengembalikan hak-hak korban, ia tidak mengalih-pindahkan hak negara terhadap arsip ini, sehingga para korban hanya mendapat akses terbatas. Terlebih lagi, meskipun arsip tersebut mencatat korban pengawasan negara, mereka juga berkaitan dengan para anggota aparat keamanan. Dengan aspek gandanya, pengungkapan arsip tidak bisa dikatakan semata-mata dilakukan demi hak para korban. Tujuan yang lain adalah untuk “menjamin dan mendorong penilaian kembali terhadap dinas keamanan negara Lihat Amos Elon, “East Germany: Crime and Punishment”, New York Review of Books, 14 Mei 1992; Stephen Kinzer, “East Germans Face Their Accusers”, New York Times Magazine, 12 April 1992; “Ex-E. German Security Police Moved Over 100,000 Files Abroad”, Reuters Library Report, 29 April 1991, tersedia di Lexis, News Library – Wires; Richard Meares, “German Debates How to Open Pandora’s Box of Stasi Files”, Reuters North American Wire, 22 April 1991, tersedia di Lexis, News Library – Wires. 91 Lihat Joachim Gauck, Die Stasi-Akten, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1991. 92 Brochure of the Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the Former German Democratic Republic on the Task, Sructure and Work of This Authority. Kalimat serupa tampil dalam pendahuluan undang-undang arsip Stasi. Lihat Act Regarding the Records of the State Security Service of the Former German Democratic Republic, 20 Desember 1002. 93 Hal ini menjadi subjek banyak eksplorasi jurnalistik yang substansial; lihat misalnya Jane Kramer, Letter from Berlin, New Yorker, 25 November 1991; Jane Kramer, Letter from Europe, New Yorker, 25 November 1992; Timothy Garton Ash, The File: A Personal History, New York: Random House, 1997. 90 33 secara historis, politis dan juridis”.94 Dengan demikian, arsip ini digunakan pula untuk “pembersihan” administrasi negara.95 Hasil kerja komisi independen yang semula ditujukan untuk mengatur akses terhadap arsip Stasi segera dijadikan cara untuk penyingkiran para kolaborator. Begitu kebijakan ini mulai dijalankan, UU arsip Stasi ini tidak sanggup mencapai sasarannya. Pertanyaan tentang apa kepedulian masyarakat terhadap arsip tersebut tidak bisa dijawab secara abstrak; dan tidak bijaksana untuk beranggapan bahwa terdapat konsensus masyarakat tentang pengungkapan arsip tersebut. Bahkan para korban memiliki konflik kepentingan berkaitan dengan arsip tersebut, namun undang-undang yang mengatur arsip tersebut tidak memberikan panduan untuk penyelesaiannya. Ketika pada masa transisi arsip negara sekali lagi digunakan untuk menyingkirkan orang-orang dari kehidupan masyarakat, bayang-bayang masa lalu yang penuh penindasan sekali lagi jatuh di atas masyarakat tersebut. Arsip siapa dan kebenaran siapa? Siapa yang paling berkepentingan dengan sejarah versi lama? Hingga sejauh mana arsip rezim lama merupakan “hak” mereka yang namanya tercantum di dalamnya?96 Atau apakah sebaiknya akses diberikan bagi pihak ketiga, seperti jurnalis, sejarawan dan lain-lainnya? Arsip-arsip rezim lama ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak hanya berkaitan dengan para pelaku dan korban. Penyelesaian dilemadilema tersebut memerlukan akomodasi terhadap kepentingan masyarakat dan individu dalam mengungkapkan masa lalu, sambil juga melindungi hak-hak privasi, dan juga kepentingan kemasyarakatan lainnya dalam mengendalikan akses. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang mengatur akses korban juga harus mengatur akses ke arsip-arsip tersebut untuk tujuan lain yang lebih sensitif. Pengalihan sejarah rezim lama ke tangan-tangan pribadi, seperti terjadi di Jerman-bersatu, merupakan bentuk respon kritis terhadap rezim lama. Jika sebelumnya seluruh informasi berada di tangan negara, kebijakan negara penerus ini adalah untuk mengalihkannya ke pihak lain. Cekoslowakia menggunakan pendekatan sebaliknya, karena rezim penerus pun tetap mempertahankan kendali negara terhadap arsip-arsip lama. Di Republik Ceko, seperti di Jerman, pada dasarnya prinsip yang memandu tindakan terhadap arsip-arsip lama adalah pengungkapan: tampak dalam kebijakan resmi yang disebut “lustrace” atau “lustration” (lustrasi), dari bahasa Latin lustrare “menyorot” masa lalu.97 Namun, sejak awal transisi, tujuan dan risiko lustrasi tampak jelas, karena pembukaan arsip-arsip lama bisa berarti mengklarifikasikan masa lalu, namun juga bisa menyingkirkan para mantan Komunis dan kolaborator dari kehidupan politik. Sebenarnya aneh bahwa keterbukaan yang lebih besar masih akan berakhir dengan penyingkiran politik. Pada pemilihan umum bebas yang pertama, masih dalam bayang-bayang arsip itu, arsip-arsip tersebut menjadi ujian politik utama bagi demokrasi. Ketika arsip-arsip tersebut digunakan sebagai cara “pemaksaan” untuk mendorong para kandidat politik menarik diri atau mendiskualifikasikan diri sendiri, timbul kontroversi yang sedemikian besar sehingga perlu disusun undang-undang untuk mengatur arsip tersebut. Dalam undang-undang lustrasi ini, akses terhadap arsip-arsip tersebut tetap berada di bawah kendali pemerintah secara total. Yang lebih parah adalah bahwa komisi yang mengontrol arsip-arsip itu dengan tujuan lustrasi juga diberikan kekuasaan untuk memutuskan 94 UU Arsip Stasi, § 1 (2). Ibid., § 1 (3). 96 Misalnya di Polandia, “hak” untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap dokumen dalam arsip diberikan kepada para “korban”, yang didefinisikan sebagai orang yang “secara rahasia datanya dikumpulkan oleh aparat keamanan secara sengaja”. Lihat The Polish Acces to Files Act of 1998. 97 Screening (“Lustration”) Law; Act No. 451/1991 (Cekoslowakia, 1991). 95 34 apakah orang-orang yang dilustrasi akan dicopot dari jabatan mereka.98 Kekuasaan untuk menentukan tentang kebenaran masa lalu, selain untuk membentuk domain politik masa kini, dikonsentrasikan pada institusi yang sama – yang seperti pada masa komunisme, pada Kementerian dalam Negeri. Peninggalan sejarah yang berkelanjutan ini juga terjadi di negaranegara lain di wilayah ini. Lustrasi menunjukkan dengan jelas garis tipis antara politik ingatan dan politik pengungkapan. Institusi yang dahulu pada masa komunisme menggunakan dokumentasi negara sebagai senjata untuk menindas, kini tetap melakukan hal yang sama pada masa transisi. Sementara pada masa lalu, arsip-arsip tersebut mendokumentasikan tuduhan subversi, kini yang didokumentasikan adalah tuduhan kolaborasi. Di Eropa Timur, arsip-arsip lama ternyata masih digunakan untuk mengontrol politik. Sejarah masa lalu ini masih digunakan untuk menghukum, menyingkirkan dan mendiskualifikasi. Bayangan tentang pencopotan massal karena tidak “bersih diri” ini, yang mengulang sejarah masa lalu, mengingatkan kita pada pandangan Marxis tentang keberulangan sejarah. Apa yang tampak dalam masa transisi di wilayah ini adalah bahwa pertanyaan tentang bagaimana cara mengatur arsip-arsip lama tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang apa peluang penggunaannya di masa transisi. Dalam masa perubahan politik yang radikal, usaha pencarian keadilan historis menggarisbawahi apa yang dikatakan sebagai kebenaran. Meskipun tampak paling jelas pada masa transisi, hal ini juga dapat ditemukan dalam sistem demokrasi dan hukum pada masa biasa. Aturan yang mengatur pengetahuan dalam hukum selalu bergantung pada tujuan dan kegunaannya; aturan menunjukkan kaitan pengetahuan dengan prospek penggunaannya menurut hukum. Mak, pertanyaan yang relevan dalam hukum menjadi: pengetahuan digunakan untuk mendefinisikan dan melaksanakan klaim, hak dan kewajiban hukum yang mana? Kedaulatan hukum membentuk kaitan antara pengetahuan dan kekuasaan. Jadi, bila pengetahuan sejarah menjadi dasar bagi peradilan pidana, hukum Amerika mensyaratkan standar pembuktian yang tertinggi “tidak ada keragu-raguan”. Untuk keperluan publik lainnya, seperti syarat untuk partisipasi dalam lingkup publik, pembuktiannya haruslah “dengan bukti yang jelas dan meyakinkan”. Terakhir, pengetahuan sejarah yang menjadi dasar hak atau kewajiban perdata harus didukung oleh “banyaknya bukti yang mendukung”, standar kebenaran yang paling banyak ditaati oleh jurnalis dan sejarawan. Dalam tinjauan konstitusionalnya terhadap lustrasi, Pengadilan Konstitusional Cekoslowakia memutuskan bahwa pertanyaan tentang aturan pembuktian manakah yang berlaku terhadap arsip-arsip negara tergantung pada keterandalan dan peluang penggunaannya. Meskipun ia menegaskan konstitusionalitas undang-undang lustrasi, beberapa bagian arsip dianggap tidak meyakinkan, sehingga tidak konstitusional untuk dijadikan dasar pengekangan hak-hak politik seseorang.99 Standar pengetahuan sejarah sebagai masalah konstitusional dikaitkan dengan kegunaan arsip-arsip tersebut. Dalam keputusannya, pengadilan menarik garis tipis antara diskontinuitas dari sistem totaliter yang lama dan kedaulatan hukum. Prinsip keadilan historis bukan pertanyaan yang bisa dijawab secara abstrak, namun dipandu oleh berbagai standar pembuktian yang berkaitan dengan masalah politik tertentu. Pertanyaan tentang aturan apa yang mengatur akses terhadap arsip rezim lama bergantung pada prospek penggunaannya untuk kepentingan politis. Pendekatan ini menyerupai pendekatan kasus demi Ibid., Pasal 4 dan 11 (memberikan akses bagi Kementerian dalam Negeri Federal terhadap arsip-arsip dan menugaskan kepada Komisi Kementerian dalam Negeri Federal untuk mendapatkan temuan). 99 Costitutional Court Decision on the Screening Law, Ref. No. P1. US1/92 (Cekoslowakia, 1992). 98 35 kasus terhadap informasi pemerintah, seperti model Amerika, dan bukannya aturan yang berlaku umum.100 Bayang-bayang sejarah negara totaliter yang masih menghantui negara-negara tersebut dapat dilihat dari usaha terus menerus untuk menyikapi peninggalan arsip-arsip dari rezim lama. Setelah puluhan tahun penindasan, perubahan politik berarti pembukaan arsip-arsip lama, namun hal tersebut tidak dengan sendirinya menciptakan masyarakat terbuka. Penciptaan kedaulatan hukum yang baru tentang arsip-arsip lama ini pada dasarnya bersifat paradoksal, karena hal ini berarti mempertahankan kontinuitas legal seutuhnya dengan rezim lama, sementara perubahan aturan yang mengatur akses terhadap arsip tersebut sehingga lebih terbuka merupakan bentuk diskontinuitas yang mengarah ke liberalisasi. Arsip-arsip rezim lama memiliki kekuatan simbolis yang tinggi, yang menunjukkan peninggalan totalitarianisme yang paradoksal: pada saat yang sama mengakui rezim represif sekaligus menjanjikan pengetahuan yang berpotensi untuk melakukan transformasi. Kebebasan Informasi: Menegaskan Akses di Masa Depan Rezim kebenaran yang dikaitkan dengan negara keamanan bersistem totaliter memiliki implikasi berlanjut bagi pendekatan terhadap informasi pemerintah pada masa transisi. Hal ini terlihat dalam respon-respon yang diambil dalam proses liberalisasi yang terkait erat dengan konteks di wilayah yang bersangkutan. Perubahan aturan tentang akses warga masyarakat terhadap informasi merupakan respon yang kritis terhadap masa lalu yang represif. Di bawah pemerintahan totaliter, negara mengontrol arsip, dan akses diberikan secara pilih-pilih.101 Pada masa transisi, sementara pergeseran menuju demokrasi dianggap tergantung pada partisipasi masyarakat yang didasarkan pada kebebasan informasi yang dikuasai negara, terdapat dorongan politik untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap arsip negara. Bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, menyeimbangkan akses informasi dengan privasi merupakan hal yang sukar. Kebebasan informasi diatur oleh kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum menekankan keseimbangan hak-hak untuk kebebasan informasi dan ekspresi, dan hak-hak individu lainnya, selain kepentingan negara.102 Di Amerika Serikat, dokumentasi pemerintah diatur oleh hukum yang melindungi kebijakan informasi pemerintah yang terbuka, sementara juga melindungi kepentingan privasi individual. Menurut hukum Amerika, arsip-arsip lembaga negara yang tidak dirahasiakan untuk alasan privasi atau keamanan nasional pada prinsipnya terbuka bagi semua warga. Pertentangan kepentingan yang mungkin terjadi akan diselesaikan melalui uji perimbangan: antara privasi individual dan kepentingan masyarakat untuk penungkapan.103 Di Amerika 100 Untuk analisis komparatif, lihat Wallach, “Executive Powers of Prior Restraint over Publication of National Security Information: The UK and USA Compared”, International and Comparative Law Quarterly 32 (1983): 424. 101 Untuk pembicaraan tentang pendekatan rezim lama, lihat Truth and Justice, The Delicate Balance, 75-77 (dikutip di catatan kaki 79 di atas). 102 Untuk perimbangan dalam hukum internasional, lihat The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information (disahkan 1 Oktober 1995), Pasal 19. 103 Lihat The Freedom of Information Act, U.S. Code, jilid. 5 bagian 552 (b) (1993) (memberikan pengecualian bagi arsip personil, medis dan penegakan hukum yang merupakan pelanggaran privasi). Lihat juga Privacy Act of 1974, U.S. Code, jilid 5 bagian 552 (1993); H. Rpt. 03-1416. Lihat umumnya Frederick M. Lawrence, “The First 36 Serikat, privilese “informan” mungkin analog dengan masalah kolaborator polisi rahasia di Eropa Timur. Bahkan bila arsip kepolisian yang semula dirahasiakan di Amerika Serikat akhirnya diungkapkan, pemerintah berhak untuk menjaga kerahasiaan informannya dengan menutupi nama-nama merka.104 Respon terhadap warisan masa Sosialis bisa dianggap “kritis” yaitu dengan usaha rezim penerus untuk merekonstruksi lingkup publik dan privat. Usaha rekonstruksi ini dilakukan terutama melalui pengakuan hak-hak konstitusional terhadap privasi dan kebebasan informasi. Banyak dari perlindungan konstitusional yang baru ini secara eksplisit merespon masalah ketiadaan privasi di masa rezim lama dengan membatasi sejauh mana pemerintah baru dapat mengumpulkan informasi dari warga mereka. Sebagai contoh, konstitusi Ceko dan Slowakia menyatakan “semua orang berhak mendapat perlindungan dari pengumpulan atau publikasi tanpa izin, atau penyalahgunaan lain, dari data pribadi mereka”.105 Konstitusi Slovenia melarang “penggunaan data pribadi yang bertentangan dengan tujuan pengumpulannya”.106 Konstitusi Hungaria menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menjaga nama baik, bahwa privasi rumah dan korespondensinya tidak dilanggar, dan perlindungan data pribadinya”.107 Konstitusi Kroasia menyatakan “Tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, data pribadi hanya bisa dikumpulkan diproses dan digunakan bila dilakukan berdasarkan hukum”.108 Namun, meskipun terdapat pernyataan-pernyataan ini, tanpa aturan lebih lanjut, usaha untuk mengkonstitusionalkan pembatasan kendali pemerintah atas dokumentasi tampaknya tidak akan bisa dijalankan, karena tidak ada larangan bagi pemerintah untuk mengumpulkan data atau menentukan standar untuk mengatur kearsipan. Batasan konstitusional tersebut tampaknya hanya mensyaratkan kedaulatan hukum yang paling sederhana – bahwa pengumpulan data dilakukan berdasarkan hukum. Batasan konstitusional lainnya terhadap data pemerintah akan membatasi pengumpulan hanya atas dasar kesukarelaan. Konstitusi Rusia yang baru menyatakan bahwa “adalah hal terlarang untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan menyebarluaskan informasi tentang kehidupan pribadi seseorang tanpa persetujuannya”.109 Konstitusi Estonia, serupa dengan itu, melarang “pemerintah negara atau lokal dan pejabat-pejabatnya untuk mengumpulkan atau menyimpan informasi tentang kepercayaan warga Estonia secara bertentangan dengan kemauannya”.110 Pengendalian terhadap penciptaan data negara adalah satu cara konstitusi di wilayah tersebut mengubah sejarah masa lalu. Idenya adalah dengan membatasi akses negara terhadap individu, dan dengan demikian menarik garis baru untuk menciptakan suatu lingkup privat. Pada saat mereka berusaha mendefinisikan kembali kendali terhadap individu dan privasi mereka, konstitusi-konstitusi transisional juga memulai transformasi kritis tentang akses warga negara terhadap negara dan memperluas kebebasan ini. Misalnya, konstitusi Amendment Right to Gather State-Held Information”, Yale Law Journal 89 (1980): 923. Untuk pembicaraan tentang perimbangan ini dalam konteks historis, lihat Charles Reich, “The New Property”, Yale Law Journal 73 (1964): 733. 104 Lihat Roviaro v. United States, 353 US 53 (1957). 105 Konstitusi Republik Czek, Pasal 10, konstitusi Slowakia, Pasal 19. 106 Konstitusi Slovenia, Pasal 38 107 Konstitusi Republik Hungaria, Pasal 59. 108 Konstitusi Republik Kroasia, Pasal 37. 109 Konstitusi Federasi Rusia, Pasal 24 (1). 110 Konstitusi Estonia, Pasal 42. 37 Rusia mewajibkan pemerintah pusat dan lokal untuk “memberikan bagi setiap warga negara akses terhadap semua dokumen dan bahan-bahan yang terkait dengan hak dan kebebasannya”.111 Konstitusi Slovenia menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk mendapatkan data pribadinya”.112 Konstitusi Estonia memberikan hak bagi warga negara untuk mendapatkan informasi tentang dirinya “yang dimiliki oleh otoritas negara atau pemerintah lokal”.113 Menurut Konstitusi Bulgaria, “warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari otoritas atau badan negara, tentang hal-hal yang secara sah merupakan kepentingan mereka, dengan syarat bahwa informasi tersebut bukanlah rahasia negara dan tidak melanggar hak-hak orang lainnya”.114 Perubahan konstitusional yang dielaborasikan setelah masa komunisme menunjukkan usaha-usaha bersama untuk memberikan batas baru bagi akses negara terhadap warga negara dan memberikan akses lebih besar bagi warga negara. Dalam transisi pasca-totaliter, respon transformatif dan kritis terhadap pelanggaran negara di masa lalu adalah dengan mencabut kekuasaan negara yang semula disalahgunakan dan membatasi peluang penyalahgunaan dengan mengkonstitusionalkan hak-hak individual terhadap privasi dan akses informasi. Respon kritis dengan menciptakan standar kebebasan informasi ini merupakan langkah maju menuju masyarakat yang lebih terbuka. Perdebatan tentang arsip dari masa komunisme menunjukkan sejauh mana arti pertanggungjawaban sejarah dalam masa transisi terkait dengan sifat ketidakadilan di masa lalu. Keadilan historis setelah pemerintahan Komunis, seperti setelah masa pemerintahan represif lainnya, berusaha untuk mengungkapkan dokumentasi pelanggaran yang dilakukan oleh negara, yang semula ditutup-tutupi. Namun, terdapat perbedaan. Pada transisi pascamiliter, ketika kediktatoran di masa lalu bertindak dengan impunitas sepenuhnya dan bahkan tidak bersedia mengakui keberadaan pelanggaran, keadilan historis memerlukan konstruksi sejarah negara; suatu penyusunan dokumentasi, yang utamanya didapatkan dari kesaksian para korban. Di bekas blok komunis, tidak dilakukan penciptaan narasi resmi demikian, karena dokumentasi telah banyak tersedia; keadilan historis berarti membuka arsip-arsip sejarah yang telah terkumpul. Dalam transisi pasca-militer, perubahan institusional yang dilakukan oleh rezim yang baru terutama merespon ketidakpastian yang diakibatkan tiadanya dokumentasi resmi, dan mengkonsentrasikan kekuasaan pada institusi yang ditugaskan untuk menyelidiki dan mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. Perubahan lain pada lingkup legislatif dan regulatoris, terutama tentang penjagaan nama baik, dilakukan untuk melindungi aktoraktor negara dalam penyelidikan dan penerbitan informasi, terutama pidato politik, meskipun hal ini mungkin harus dibayar dengan hak-hak dan kepentingan lain dalam masa transisi. Pada transisi pasca-komunis, perubahan institusional diarahkan untuk mengendalikan penyelidikan publik, melindungi privasi individual dan mengkonstitusionalkan hak warga negara untuk mengakses informasi. Respon yang berbeda ini menunjukkan bahwa isi keadilan historis disusun berdasarkan konteks transisi dan peninggalan pemerintahan represif. Arti keadilan historis sendiri amatlah terkait dengan penindasan di masa lalu, terutama penggunaan sejarah dan pengetahuan oleh rezim di masa lalu. 111 Konstitusi Federasi Rusia, Pasal 24(2). Konstitusi Slovenia, Pasal 38. 113 Konstitusi Estonia, Pasal 44. 114 Konstitusi Republik Bulgaria, Pasal 41(2). 112 38 Pengalaman pada masa transformasi politik menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya hukum, negara-negara biasanya melakukan usaha untuk mendapatkan pertanggungjawaban historis. Pertanyaan yang timbul adalah: apa kaitan keadilan historis pada masa transisi dan pertanggungjawaban dalam negara-negara demokratis yang sudah mapan? Jawabannya sebagai berikut: respon hukum terhadap tirani, yang dibuat pada masa transisi, menyorot nilai-nilai latar belakang yang mendasari pengaturan terhadap dokumentasi dan informasi resmi pada sistem demokratis. Dilema transisional dan respon legal terkait yang dibicarakan di atas menunjukkan isu-isu dan resolusi yang sering kali tidak hanya terbatas pada masa-masa transisional. Misalnya, pada masa kontemporer, batasan antara lingkup “publik” dan “privat” sering kali tidak jelas, dan pertanyaan tersebut merupakan perdebatan publik. Respon historis memiliki dampak jangka panjang yang melampaui individu-individu yang terkait, dan mempengaruhi seluruh masyarakat dan negara. Bahkan, respon historis ini membantu menyusun identitas politik kolektif. Respon-respon terhadap dilema transisional di atas bisa membantu menggambarkan bagaimana masyarakat mempertimbangkan signifikansi batasan-batasan tersebut dalam masa-masa normal. Hukum Sejarah “Sejarah akan menjadi hakim” – kebenaran akan bertahan seiring waktu. Pepatah ini menggambarkan intuisi masyarakat tentang kaitan antara interpretasi sejarah dan waktu, yang menunjukkan bahwa kebenaran sejarah akan berkembang seiring waktu. Hal ini tampak benar minimal pada tingkat deskriptif. Sering kali beberapa generasi datang dan pergi, sebelum masyarakat dapat menghadapi sejarahnya. Meskipun usaha untuk mencapai keadilan historis tampak sangat giat dilakukan pada masa transisional, arti keadilan tersebut sering kali ditinjau kembali dan bisa berubah. Seiring perjalanan waktu, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan perkembangan sejarah memberikan pengaruhnya pada interpretasi sejarah, yang memungkinkan perubahannya. Jadi, perjalanan waktu menimbulkan dilema tentang pencapaian keadilan historis. Sejauh mana pemahaman transisional tentang kebenaran sejarah, baik yang diciptakan melalui pengadilan individual, komisi atau proses lainnya dapat bertahan? Apakah perubahan-perubahan yang terjadi menyulitkan kemungkinanan diciptakannya pemahaman yang tunggal dan tetap tentang peninggalan represi di masa lalu? Apakah ini berarti bahwa keadilan historis transisional bersifat hanya sementara dan politis? “Perdebatan Sejarawan”: Menarik Garis Pembatas Masa Lalu Penciptaan sejarah transisional yang sudah dijelaskan sejauh ini menggambarkan signifikansi baik peninggalan politik maupun kerangka politik kontemporer dalam membentuk sejarah dan ingatan kolektif. Namun, konstruksi demikian pun memiliki keterbatasannya. Perdebatan tentang revisionisme sejarah Perang Dunia Kedua menggambarkan batasan tinjauan sejarah yang bisa diizinkan. Paradigma permasalahan keadilan historis setelah berlalunya waktu adalah usaha Jerman masa kini untuk mengintegrasikan masa lalunya ke dalam sejarah nasional. Inti perdebatan Jerman kontemporer itu, setengah abad setelah berakhirnya perang, adalah pertanyaan tentang apakah ada pemahaman sejarah yang permanen. Historikerstreit, 39 “perdebatan sejarawan”, ini diawali pada tahun 1985, dengan terbitnya The Guilt-Laden Memory tulisan Joachim Fest, yang menantang pemahaman umum tentang perang dan menyatakan bahwa musuh sebenarnya adalah Uni Soviet dan bukan Jerman. Sejarawansejarawan lain turut serta dalam perdebatan itu dengan tantangan serupa terhadap pandangan tentang tanggung jawab Nazi. Dalam The Past Which Will Not Pass On, Ernst Nolte membandingkan kejahatan Nazi dengan tindakan Soviet dalam Gulag mereka, dan menjelaskan melalui perbandingan bahwa tidak ada hal yang luar biasa dari penindasan oleh Jerman Nazi. Jika Fest dan Nolte, melalui karyanya masing-masing, berusaha menormalisasi pemahaman umum tentang tanggung jawab masa perang Jerman, maka Two Kinds of Ruin: The Shattering of the German Reich and the End of European Jewry karya Andreas Hillgruber merupakan tantangan yang lebih kuat lagi terhadap pandangan umum, karena tinjauan Hillgruber ini menempatkan Jerman pada posisi korban genosida, bukan pelakunya.115 Tantangan yang muncul dari sudut pandang akademisi ini berjalan bersamaan dengan usaha politik dari pemerintahan Helmut Kohl yang tampaknya juga berusaha untuk mengubah pandangan umum tentang masa lalu Jerman. Dengan melakukan kunjungan diplomatik secara bersamaan pada dua tempat – kamp konsentrasi sekaligus pemakaman militer Bitburg – para pejabat tinggi Jerman memberikan pesan bahwa militer Jerman yang menjadi korban perang setara dengan penduduk sipil yang menjadi korban penindasan. Satu contoh lain setelah keruntuhan Soviet adalah tinjauan tentang keburukan Gulag, yang bersumber pada arsip-arsip komunis yang baru dibuka, dan menempatkan baik fasisme maupun komunisme sebagai “dua jenis totalitarianisme”.116 Apa yang dipermasalahkan oleh tantangan-tantangan tersebut? Perdebatan sejarawan ini dikatakan oleh filsuf Jerman Jürgen Habermas sebagai “kampanye untuk revisionisme sejarah Nazi”.117 Pertanyaan yang penting adalah apakah setelah berlalunya waktu, tinjauan sejarah tentang genosida terhadap kaum Yahudi pada Perang Dunia Kedua akan dipertahankan sebagai tinjauan resmi, atau apakah ia bisa berubah secara sah, mungkin dengan memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia kontemporer.118 Versi-versi baru tentang penindasan pada masa perang menantang versi sejarah yang sudah mapan pada beberapa aspek: tentang kesalahan yang terjadi, status dan tanggung jawab pelaku, dan hak-hak korban. Signifikansi perdebatan hermeneutik tentang masa lalu ini berada pada implikasinya terhadap pemahaman negara tentang dirinya. Beberapa sejarawan, seperti Charles Maier, menunjukkan bahwa signifikansi perkembangan sejarah ini terletak pada “genosida komparatif”. Tantangan yang diberikan ini adalah kepada pemahaman yang umum tentang pemusnahan massal oleh Jerman yang sistematis dan terkalkulasi terhadap musuh-musuhnya sebagai sui generis. Perbandingan dengan penindasan Soviet melemahkan pandangan mapan tentang tanggung Untuk tinjauan tentang perdebatan sejarawan, lihat Charles S. Meier, The Unmasterable Past: History, Holocaust and German National Identity, Cambridge: Harvard University Press, 1989, 9-33. Lihat juga Perry Anderson, “On Emplotment: Two Kinds of Ruin”, dalam Probing the Limits of Representation, (ed.: Saul Friedlander), Cambridge: Harvard University Press, 1992. 116 Stephane Courtois, Nicholas Werth, Jean-Louis Panné et al., Le Livre Noir de Communisme: Crimes, Terreur, Répression, Paris: Laffont, 1998. 117 Jürgen Habermas, The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historian’s Debate (ed. dan penerjemah Shierry Weber Nicholsen), Cambridge: MIT Press, 1989. 118 Lihat umumnya Maier, Unmasterable Past. 115 40 jawab pidana Jerman ini. Sejarawan dan filsuf lain seperti Habermas dan Martin Broszat119 menganggap bahwa yang sedang dipermasalahkan adalah suatu perspektif yang lain tentang keadilan historis, yang bukan berkaitan dengan interpretasi tanggung jawab pelaku, namun dengan dampak yang signifikan terhadap hak-hak historis para korban. Keadilan historis memiliki potensi restoratif, dengan potensi untuk mengembalikan harga diri para korban dan pada akhirnya bahkan keadilan korektif. Apakah pandangan yang berubah tentang Holocaust dan penindasan lainnya ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan seiring perjalanan waktu? Apakah keadilan historis berlaku permanen sepanjang masa? Masalah perubahan pandangan ini timbul dalam konteks perdebatan ilmiah yang jauh lebih luas terhadap interpretasi dan representasi sejarah. Penyusunan teori sejarah kontemporer mengasumsikan bahwa perubahan interpretasi tidak dapat dihindarkan, apalagi seiring perjalanan waktu; perdebatan sejarawan di atas merupakan tantangan dalam bentuk perubahan interpretasi. Dalam model teoretisasi ini, interpretasi sejarah tidak bisa dianggap netral atau objektif, namun selalu berada dalam konteks politik tertentu.120 Namun, masalah batasan parameter yang diizinkan terhadap karakterisasi penindasan masa Perang Dunia Kedua, setelah jangka waktu yang panjang, menjadi kerangka perdebatan interpretif ini dalam bentuknya yang paling ekstrem. Ketika pertanyaan tentang apakah ada prinsip yang mendefinisikan batasan penafsiran sejarah yang diizinkan terhadap kekejaman Nazi, perdebatan teoretis ini menjadi terfokus: ada prinsip untuk memandu kebenaran sejarah, bahkan sejarah yang kebenarannya tampak sedemikian jelas? Apakah tidak ada batasan terhadap interpretasi sejarah, relativisasi, revisionisme dan pada akhirnya “bantahan” sejarah? Jika tidak untuk kasus genosida, lalu untuk kasus apa ia diizinkan? Meskipun tampaknya interpretasi sejarah untuk kasus-kasus tertentu tidak bisa berubah seiring perjalanan waktu, tetap ada pertanyaan tentang apakah ada batasan pada jenis narasi yang bisa dikisahkan. Bahaya reinterpretasi peristiwa-peristiwa politik yang penting – yang merupakan inti perdebatan para sejarawan – menggarisbawahi apa yang menjadi taruhan dalam transisi yang sukses, transisi dari sistem yang tidak adil dan menindas ke sistem demokrasi liberal. Perubahan politik dan sosial mensyaratkan adanya perubahan interpretasi. Yang berubah adalah bagaimana manusia menginterpretasikan hal yang terjadi di sekitar mereka. Namun, apa yang ditunjukkan oleh perdebatan sejarawan ini adalah bahwa garis antara interpretasi tidak selalu jelas. Usaha untuk mengendalikan interpretasi sejarah menunjukkan signifikansi usaha untuk memelihara suatu narasi yang liberal – dalam menghadapi tantangan baru rasisme dan xenofobia. Memelihara Keadilan Historis Melalui Hukum Meskipun sering kali timbul tantangan bagi interpretasi sejarah yang revisionis, pada akhirnya, yang dapat membatasi interpretasi sejarah yang diizinkan tidak datang dari akademisi, 119 Lihat martin Broszat dan Saul Friedlander, “A Controversy about the Historicization of National Socialism”, New German Critique 44 (1988): 81-126. 120 Lihat Hans Georg Gadamer, “The Historicity of Understanding”, dalam The Hermeneutic Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present, (ed.: Kurt Mueller-Vollmer), New York: Continuum Publishing, 1988, 270. 41 melainkan dari hukum. Bahkan bila penciptaan sejarah dilakukan secara tidak resmi, proses hukum sering kali dipergunakan untuk memelihara tinjauan sejarah yang sudah diciptakan tersebut. Suatu tinjauan terhadap respon legal tersebut menunjukkan bagaimana narasi sejarah menjadi tertanam. Bagaimana cara mempermanenkan suatu tinjauan sejarah tentang masa lalu yang buruk? Masyarakat transisional sering kali berusaha menanamkan tinjauan sejarah tentang penindasan di masa lalu, dan seperti ditunjukkan pengalaman di atas, penciptaan dan pemeliharaan tinjauan sejarah tersebut dilakukan melalui hukum. Yang paling jelas adalah dengan pengadilan dan komisi kebenaran yang digunakan untuk menciptakan rekaman sejarah resmi, yang dengan sendirinya membatasi kemungkinan adanya versi lain dari sejarah. Namun, undang-undang amnesti, dengan fungsinya untuk “membungkam”, juga berguna untuk melindungi satu versi sejarah yang resmi. Pemeliharaan terhadap narasi nasional tertentu bergantung pada pengendalian versi sejarah yang resmi, selain versi-versi sejarah lainnya. Pemeliharaan kendali tersebut menjadi semakin sukar seiring perjalanan waktu. Suatu ilustrasi yang bisa dicontohkan di sini adalah bangkitnya kembali isu penghilangan di Argentina, lebih dari satu dekade setelah transisi, dengan pengakuan seorang kapten angkatan laut yang ikut serta menghilangkan orang.121 Maka, meskipun terdapat konsensus pada saat transisi untuk membatasi konfrontasi terhadap pelanggaran di masa lalu, pengakuan satu orang ini membuka kembali permasalahan ini. Tantangan yang muncul belakangan ini menunjukkan ketidakpuasan dengan kompromi transisional – dan kesediaan untuk menerima tinjauan lainnya. Proses ajudikasi dengan standar pembuktiannya juga memungkinkan penciptaan dan pemeliharaan satu versi tinjauan sejarah. Prinsip-prinsip ajudikasi hukum, kasus demi kasus, membatasi parameter perdebatan sejarah. Salah satu strategi adalah prinsip “pengakuan yudisial” (judicial notice), agar pengadilan dapat menerima kebenaran fakta-fakta tertentu tanpa pembuktian formal. Fakta-fakta yang dapat “diakui” secara yudisial adalah yang dikenal umum oleh masyarakat atau dapat ditentukan melalui sumber-sumber biasa. Contoh penerapan prinsip ini berkaitan dengan penindasan pada masa Perang Dunia Kedua terjadi sejak pengadilan Nuremberg, ketika tribunal pada waktu itu wajib melakukan “pengakuan yudisial” terhadap “fakta-fakta yang merupakan pengetahuan umum”.122 Kasus-kasus Amerika Serikat tentang pelanggaran masa perang menganut prinsip pengakuan yudisial terhadap penindasan. Dalam menggunakan prinsip ini, pengadilan menyatakan bahwa fakta-fakta tersebut sedemikian dikenalnya sehingga tidak bisa dibantah.123 Melalui prinsip ajudikatif pengakuan yudisial, hakim mengakui peristiwa-peristiwa sejarah yang diketahui dan tidak dapat dibantah di tingkat masyarakat dan memutuskan bahwa kontroversi sejarah berada di luar tantangan legal yang sah dan di luar perdebatan fakta sejarah yang perlu diperhatikan. Melalui Lihat Calvin Sims, “Argentine Tells of Dumping Dirty War Captives in the Sea”, New York Times, 13 Maret 1995, rubrik Internasional. Untuk studi mendalam tentang “efek Scilingo”, lihat Marguerite Fetlowitz, A Lexicon of Terror: Argentina and the Legacies of Torture, New York: Oxford University Press, 1998. 122 Lihat “Procedure, Practice and Administration” dalam Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, Vol. 15, Washington, D.C: Government Printing Office, 1953, 568-70. Di pengadilan-pengadilan Amerika, proses ini berlaku menurut Federal Rule of Evidence 201. 123 Lihat misalnya United States v. Kowalchuk, 773 F2d 488 (3d Cir. 1985) (“Kekejaman tirani yang dialami warga negara sipil oleh pasukan pendudukan Nazi pada masa Perang Dunia Kedua sedemikian terkenalnya sehingga tidak perlu diberikan kutipan”); Succession of Steinberg, 76 S2d 744 (L. Ct. App. 1955) (memberikan pengakuan yudisial terhadap eksekusi yang dilakukan di Eropa yang dikuasai Nazi). 121 42 mekanisme ini, ingatan para korban individual dapat secara formal diakui, diterima dan dimuat ke dalam sejarah kolektif yang luas dan diterima secara formal. Pemantapan suatu versi tinjauan sejarah dapat dilakukan dengan perundang-undangan yang mengatur dan mengendalikan versi-versi lainnya. Salah satu cara tentang bagaimana proses ini dijalankan dalam masa transisi, seperti dijelaskan di muka, adalah melalui undangundang amnesti yang memungkinkan peredaman secara resmi terhadap tindakan-tindakan pelanggaran di masa lalu. Karena itu, pemberian amnesti sering kali menimbulkan konflik. Beberapa pihak memprotes karena undang-undang ini membisukan para korban yang berusaha menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut, para pelaku yang menolak amnesti dan semua elemen masyarakat yang menginginkan tinjauan tentang masa lalu yang independen. Negara yang terpengaruh secara langsung oleh Nazisme juga menggunakan peraturan untuk memelihara satu versi sejarah. Sejak berakhirnya perang, banyak negara Eropa memiliki hukum perdata untuk mengambil tindakan terhadap penghinaan yang berkaitan dengan genosida masa perang. Sebagai contoh, penyebarluasan apa yang dikenal sebagai “kebohongan Auschwitz”, yaitu usaha untuk membantah Holocaust sebagai kebenaran sejarah, dianggap sebagai penghinaan yang dapat dituntut secara perdata. Undang-undang penyensoran ini dijustifikasi oleh keadilan historis bagi para korban, dan potensi dampak buruk dari versi sejarah yang lain dan berlawanan. Sejak perdebatan para sejarawan, terdapat sejumlah hukum pidana yang dirancang untuk mempertahankan pandangan yang telah ada tentang penindasan pada masa perang. Sejak sebelumnya, tulisan-tulisan kebencian rasial merupakan hal yang melanggar hukum.124 Bantahan terhadap Holocaust kemudian juga dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Menurut undang-undang yang baru itu, jika seseorang “menyetujui, membantah atau menyepelekan tindakan-tindakan genosida yang dilakukan oleh Nazi” dan bila yang dihina adalah anggota kelompok yang mengalami penindasan di bawah “Nazi atau penguasa yang kejam dan sewenang-wenang”, ia bisa dipidana. Undang-undang penyensoran ini, seperti juga hukum perdata yang sudah ada, dijustifikasi oleh kewajiban terhadap para korban dan dampak negatif dari pandangan yang berlawanan.125 Pada masa kini, Pengadilan Konstitusional Federal Jerman menyatakan bahwa pembantahan terhadap Holocaust tidak dijamin sebagai “kebebasan berpendapat” menurut undang-undang dasar. Penggunaan istilah “kebohongan Auschwitz” (Auschwitz Lüge) merupakan pelanggaran hak warga Yahudi Jerman yang bisa dihukum.126 Di Jerman, pengadilan menganggap fakta tentang terjadinya Holocaust sebagai kebenaran yang tidak memerlukan pembuktian formal.127 Demikian pula, sebuah undangundang Prancis pada tahun 1990 menjadikan “revisionisme” atau pembantahan terhadap genosida Nazi sebagai tindak pidana.128 Di Kanada, sanksi pidana serupa yang melarang “halLihat German Criminal Code §§ 130, 131 StGB. Ibid., Pasal 194 sebagaimana diperbaiki, 13 Juni 1985. Untuk analisis perundang-undangan Jerman, lihat Eric Stein, “History against Free Speech: The New German Law against the ‘Auschwitz’ and Other ‘Lies’”, Michigan Law Review 85 (1986): 277. 126 Lihat This Week in Germany, 19 April 1994; dilaporkan dalam NJW (Jerman, 1982), 1803. Lihat juga S. J. Roth, “Second Attempt in Germany to Outlaw Denial of the Holocaust”, Patterns of Prejudice 18 (1985): 46. 127 Ibid. 128 Statute of July 1990 (Perancis). Lihat juga Licra et autres c. Faurrison, Tribunal de Grande Instance (8 Juli 1981) (Recueil Dalloz, 1982); Roger Errera “In Defense of Civility: Racial Incitement and Group Libel in French Law”, dalam Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Exprssion and Nondiscrimination, ed. Sandra Coliver, Human Rights Centre, University of London, Art 19 Int’l Center Against Censorship of Essex, 1992 124 125 43 hal bohong” demikian diterapkan untuk menyensor tulisan-tulisan revisionis tentang Perang Dunia Kedua.129 Dengan bergeser dari sanksi perdata ke pidana, perundang-undangan kontemporer tidak hanya menyikapi pengaruh buruk kebohongan demikian terhadap korban-korban Perang Dunia Kedua, namun juga ke seluruh masyarakat. Menjadikan sejarah revisionis sebagai tindak pidana menunjukkan keyakinan bahwa versi-versi sejarah yang berbeda ini tidak saja merupakan penghinaan bagi para korban sebagai individu, namun juga merupakan kejahatan bagi seluruh masyarakat. Bentuk hukum yang paling tegas ini digunakan untuk menjamin suatu konseptualisasi keadilan historis: yang memberikan hak keadilan historis yang permanen bagi para korban penindasan berat oleh negara, dengan perlindungan yang dijamin dan diterapkan oleh hukum pidana. Sebagai contoh, dalam sebuah pengadilan di Prancis, pengadilan menyatakan bahwa “pembatasan kebebasan memerlukan penghargaan bagi para korban”.130 Dan sebuah kasus di Jerman menyatakan bahwa “siapa pun yang membantah pembunuhan warga Yahudi di Jerman semasa Nazi ia melakukan penghinaan bagi semua orang”.131 Namun, masih belum jelas bagaimana justifikasi ini akan bertahan seiring perjalanan waktu. Perundang-undangan kontemporer Eropa memperluas undang-undang yang semula dibuat hanya untuk mencegah bantahan terhadap Holocaust ini, untuk mencegah semua bantahan terhadap bentuk-bentuk penindasan lainnya, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, baik yang dilakukan di bawah rezim Nazi atau rezim represif selanjutnya.132 Perundang-undangan pidana kontemporer lainnya diarahkan untuk melindungi korban-korban penindasan. Undang-undang tersebut juga mendasarkan premisnya pada pandangan yang lebih luas tentang potensi dampak buruk bantahan revisionis itu, yaitu bahwa masyarakat luas memiliki kepentingan untuk memelihara suatu versi kebenaran sejarah. Hukum digunakan untuk melindungi suatu tinjauan sejarah tentang penindasan negara dengan meredam versi-versi lainnya. Sebagai contoh, di Eropa pasca-Perang Dunia Kedua, sejumlah perundang-undangan tentang hak berpendapat disusun, mengaitkan masa lalu dan masa kini, menjadikan “penyebarluasan kebencian” terhadap korban-korban penindasan masa perang sebagai tindak pidana. Undang-undang penyebarluasan kebencian mengaitkan penindasan di masa lalu dengan kejadian masa kini yang dengan cara apa pun menimbulkan perdebatan kembali tentang sejarah atau pelanggaran politik yang pernah terjadi. Normanorma anti-penyebarluasan kebencian menjadikan propaganda tentang penindasan negara di masa lalu sebagai tindak pidana. Bentuk-bentuk respon hukum yang demikian tampak jelas dalam hukum internasional yang ada. Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “segala bentuk penyebarluasan atau dukungan bagi kebencian nasional, rasial atau keagamaan yang merupakan dorongan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan (membicarakan Gayssot Law of 13 July 1990 menggambarkan pelanggaran baru untuk menantang definisi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti didefinisikan di Nuremberg). 129 Criminal Code of Canada, § 181. Kasus yang paling menonjol adalah Zundel v. The Queen 35 DLR (4th) 338, 31 CCC (3d) 97 Ont. CA.) (1987). Untuk pembicaraan tentang preseden Kanada ini, lihat “When Academic Freedom and Freedom of Speech Confront Holocaust Denial and Group Libel: Comparative Perspectives”, Boston College Third World Law Journal 8 (1988): 65. 130 Olivier Biffaud, “M. Le Pen Indesirable Dans Plusiers Villes”, Le Monde (Paris), 24 Mei 1990, tersedia di Lexis; lihat Susan Anderson, “Chronicle”, New York Times, 24 Mei 1990, bagian B, 24. 131 Ref. No. VI ZR 140/78 Enstcheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (B6H2), 160 et seq Juristenzeitung 75 (1979): 811. 132 Lihat National Institute of Rememberance Act (Polandia 1998). Ia menyatakan bahwa orang yang secara terbuka membantah “kejahatan Nazi atau komunis, atau kejahatan terhadap kemanusiaan” akan dihukum. 44 atau kekerasan” haruslah dilarang oleh hukum.133 Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menyatakan negara harus melarang “penyebarluasan pemikiran yang berdasarkan superioritas atau kebencian rasial, dorongan untuk melakukan diskriminasi rasial”.134 Pasal 20 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga menyatakan bahwa “segala bentuk penyebarluasan atau dukungan bagi kebencian nasional, rasial atau keagamaan yang merupakan dorongan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan” haruslah dilarang oleh hukum”.135 Banyak negara Eropa memiliki hukum serupa. KUHP Jerman melarang “menyerang harga diri orang lain dengan menimbulkan kebencian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat, menyerukan tindakan kekerasan terhadap mereka, atau menghina mereka, menghina dengan kebencian atau memfitnah”.136 Di Denmark, mengucapkan hinaan rasial atau etnis merupakan pelanggaran hukum pidana.137 Secara terbuka mengancam atau menyatakan “kebencian terhadap kelompok rasial, warna kulit atau kepercayaan nasional” bisa berakibat hukuman penjara hingga dua tahun di Swedia.138 Undang-Undang Hubungan Antar-Ras di Inggris menjadikan “mendorong kebencian, menerbitkan, menyebarluaskan atau secara terbuka menggunakan bahan-bahan yang mengancam, mengganggu atau menghina orang-orang lain atas dasar warna kulit, ras atau etnik” sebagai tindak pidana.139 Di Amerika Serikat, sejarah perbudakan, segregasi dan rasisme yang masih tersisa mendorong disusunnya sejumlah perundang-undangan “kejahatan kebencian”. Meskipun tradisi hukum amat melindungi kebebasan berpendapat, undang-undang anti-kebencian menambah hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan atas dasar bias rasial atau motif serupa.140 Dalam suatu tantangan konstitusional, sebuah undang-undang yang menyensor penyebarluasan kebencian ditegaskan keabsahannya karena “tindakan ini dianggap dapat merugikan individu dan masyarakat”.141 Meskipun tindakan yang dimaksud bisa berupa tindakan pribadi yang dilatarbelakangi motif rasial, dengan latar belakang sejarah penindasan oleh negara, ia memunculkan kembali penindasan dari masa lalu, sehingga ia harus lebih dikutuk. Respon yang tegas terhadap kejahatan tersebut menegaskan apa yang dicapai dalam masa-masa transisi. Penggunaan hukum untuk melindungi tinjauan sejarah tertentu bisa menimbulkan dilema, karena ia sering kali bertentangan dengan kepentingan lain dalam masyarakat yang 133 “Universal Declaration of Human Rights”, U.N. General Assembly Resolution 217 (III), Pasal 20, 10 Desember 1948. 134 “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, U.N. General Assembly Resolution 2106 (XX), Pasal 4, 21 Desember 1965 (mulai berlaku 2 Januari 1969). 135 “International Covenant on Civil and Political Rights”, U.N. General Assembly Resolution 2200a (XXI), Pasal 20, 16 Desember 1966 (mulai berlaku 23 Maret 1976). 136 German Criminal Code, Pasal 130. 137 Danish Criminal Code, § 266(b). 138 Swedish Penal Code, bab 16(8). 139 Race Relations Act 1965, § 6 (1). 140 Untuk tinjauan tentang statuta-statuta ini, lihat Anti-Defamation League, Hate Crimes Laws: A Comprehensive Guide, New York: Anti-Defamation League, 1997. 141 Wisconsin v. Mitchell, 508 US 476 (1993) (menegaskan Wisconsin Penalty Enhancement Statute, yang memberikan tambahan hukuman jika pelaku kejahatan, “secara sengaja memilih korban kejahatan atau menjadikan barang sebagai sasaran kejahatan atau terpengaruh oleh kejahatan tersebut ... sebagian atau seluruhnya karena kepercayaan atau perseppsi pelaku tentang ras, agama, warna, cacat, orientasi seksual, asal kebangsaan atau keturunan korban atau pemilik atau penghuni barang tersebut, baik apakah kepercayaan atau persepsi pelaku tersebut benar atau salah”) Wisconsin Statute 939.645 (1991-1992). 45 dikaitkan dengan negara liberal, seperti kebebasan berpendapat yang tidak terbatas.142 Penanganan dilema tersebut bervariasi pada masyarakat-masyarakat transisional yang berbeda, tergantung pada konteks politik sekaligus pada peninggalan sejarah penindasan. Misalnya, dalam skema konstitusional Jerman, dilema ini diselesaikan oleh prinsip normatif yang mengecualikan hak berpendapat yang serupa dengan penyalahgunaan propaganda rasis pada masa perang.143 “Siapa pun yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi ... untuk melawan tatanan demokratik bebas yang mendasar, akan kehilangan kebebasan tersebut”. Sebaliknya, dalam sejarah Anglo-Amerika, di mana tirani berbentuk kekangan terhadap ekspresi,144 jurisprudensinya berbeda: absolutisme dan sensor merupakan kejahatan yang utama. Yang merupakan nilai utama keadilan historis, seperti ditunjukkan praktik di atas, tidaklah universal, namun spesifik pada sejarah ketidakadilan. Respon transisional terhadap pemerintahan represif membantu menyusun norma-norma kontemporer yang membentuk diskursus politik liberal yang beragam. Usaha untuk menanamkan satu tinjauan sejarah ini sendiri menimbulkan masalah bagi liberalisme. Pertanyaan timbul dalam gelombang transisi setelah runtuhnya komunisme, ketika ada pandangan yang menganggap bahwa inilah waktu untuk menanamkan identitas kapitalisme Barat, dan dengan demikian menghentikan dialektika sejarah.145 Namun, klaimklaim demikian tidak dapat menjelaskan sejauh mana sejarah “pasca-komunis” bukanlah “pasca-sejarah”, namun terletak dalam dinamika transisional dan sejarah transisional, dalam konteks khusus akibat masa lalu yang penuh penindasan dan keadilan transisional yang menjadi konteks baru. Bukankah negara liberal secara normatif harus memungkinkan perubahan sejarah? “Keadilan Puitik”: Narasi Transisi Marilah kembali ke pertanyaan di awal bab ini: apa kaitan proses sejarah dengan transformasi politik yang meliberalkan? Bab ini diawali dengan diskusi tentang peran pernyelidikan sejarah dalam merespon peninggalan sejarah masa lalu suatu negara dan apakah terdapat kaitan antara penyelidikan sejarah di suatu negara terhadap masa lalunya yang tidak liberal dan prospek demokrasi di masa depan. Dalam analisis ini, pertanyaan normatif tentang apakah penyelidikan sejarah merupakan respon transisional yang ideal bukanlah menjadi pertanyaan yang penting; bahkan tanpa proses penyusunan sejarah secara sadar, seperti melalui pengadilan, komisi penyelidikan dan laporan, pasti akan tercipta suatu narasi sejarah. Narasinarasi transisional memiliki struktur retorisnya sendiri, yang dengan sendirinya menyusun R. v. Keegstra, 2 WWR 1 (Kanada, 1991). Konstitusi Republik Federasi Jerman (Basic Law), Pasal 1, 18, 21. 144 Lihat New York Times v. Sullivan, 376 US 254 (1964) (memberikan arti lebih luas pada Amendemen Pertama tentang prinsip bahwa perdebatan isu publik bersifat “tanpa halangan, kuat dan terbuka luas) menjunjung konstitusi mensyaratkan aturan yang melarang pejabat publik untuk mendapatkan ganti kerugian dari fitnah yang merendahkan berkaitan dengan jabatannya, kecuali bila ada “kerugian sebenarnya”. Untuk sejarahnya, lihat F. Siebert, Freedom of the Press in England, Urbana: University of Illinois Press, 1952, 1476-1776; Philip Hamburger, “The Development of the Law of Seditious Libel and Control of the Press”, Stanford Law Review 37 (1985): 661; Zechariah Chaffee Jr., Free Speech in the United States 18 (1941). 145 Lihat Francis Fukuyama, “The End of History?” National Interest, No. 16 (musim panas 1989): 3-18. 142 143 46 suatu perubahan identitas. Sejarah transisional – tinjauan tentang tirani masa lalu yang disusun pada masa liberalisasi – merupakan bentuk narasi yang khas. Narasi-narasi yang disusun pada masa transisi paling jelas membawa pesan normatif tentang kaitan sejarah dan demokrasi: garis narasi menyatakan kaitan antara relevansi pengetahuan sejarah dengan kemungkinan perubahan personal dan sosial. Tinjauan sejarah tentang transisi merupakan suatu tinjauan tentang kaitan antara pengetahuan dan pergeseran dari kediktatoran serta prospek untuk masa depan yang lebih liberal. Tinjauan-tinjauan ini memberikan suatu perasaan keadilan yang terasa “puitik”. Narasi transisional merupakan suatu bentuk atau genre sastra yang khas, yang bisa dianggap sebagai suatu campuran tragedi-komedi atau tragedi-romantik.146 Sementara narasi transisi dimulai dengan tragedi, mereka diakhiri secara komedi atau romantik. Dalam pemahaman klasik, tragedi tersusun dari elemen-elemen penderitaan yang mendalam yang dialami kelompok-kelompok besar, kota-kota dan negara, yang diikuti penemuan atau perubahan dari ketidaktahuan ke pengetahuan, suatu saat klarifikasi.147 Seperti tragedi klasik berfokus pada penderitaan individu, yang nasibnya, karena status mereka, mempengaruhi keseluruhan kelompoknya, kisah penderitaan kontemporer juga mengisahkan pengaruhnya secara luas. Sementara narasi transisi diawali secara tragis, pada satu titik, mereka bergeser ke satu keputusan untuk mengubah nasibnya yang tragis tersebut; pada kesusasteraan klasik, hal ini ditunjukkan dengan pergeseran ke tahap komedi. Penderitaan masa lalu yang dialami seluruh negara diubah sedemikian rupa sehingga berakhir dengan bahagia: perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam tragedi, peran pengetahuan hanyalah untuk memastikan nasib yang telah diketahui sejak awal. Namun tinjauan transisional diawali dengan penderitaan, ketidakadilan, perbudakan, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian, sesuatu terjadi dan orang-orang yang terlibat dalam kisah tersebut pada akhirnya menghindari nasib tragis dan sanggup bertahan dalam realitas yang baru. Dalam konvensi romantisme yang dikaitkan dengan tinjauan transisional, perubahan ini melibatkan titik balik penting tentang pengetahuan diri, di mana pengetahuan tersebut – tidak seperti dalam tragedi – menimbulkan perbaikan. Narasi transisional dalam konteks perubahan politik memiliki bentuk yang khas dan memainkan peran tertentu dalam perubahan politik. Melalui proses komisi, dalam tindakan legal, masyarakat secara keseluruhan terkait dalam benang merah transisi ini. Seperti akan dibahas di bawah, struktur transisi tampak dalam tinjauan transisi baik fiktif maupun non-fiktif. Laporan-laporan maupun karya-karya fiksi sama-sama menaati narasi tertentu yang berjalan seperti berikut ini: meskipun dalam masa rezim lama terjadi penderitaan besar-besaran, penderitaan tersebut sedemikian rupa diubah menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat, menjadi pemahaman diri yang lebih baik dan prospek yang lebih baik bagi kebertahanan demokrasi. Narasi nasional ini diawali secara tragis namun berakhir dengan penebusan seluruh masyarakat. Perhatikanlah kisah-kisah dalam laporan-laporan setelah masa penindasan. Mulai dengan judul laporan: dengan diberi judul Tidak Akan Pernah Lagi, laporan-laporan Amerika Latin ini menjanjikan bahwa mereka dapat mencegah penderitaan di masa depan. Sebagai contoh, dalam laporan pertama Komisi Nasional Orang Hilang Lihat Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton: Princeton University Press, 1957. Lihat Aristoteles, “Poetics”, dalam The Complete Works of Aristotle, Vol. 2, (ed: Jonathan Barnes), Princeton: Princeton University Press, 1984, 2323-24; Timothy J. Reiss, Tragedy and Truth: Studies in the Development of a Renaissance and Neoclassical Discourse, New Haven dan London: Yale University Press, 1980. 146 147 47 Argentina, tinjauan tentang penindasan di negara tersebut diawali dengan prolog yang menyatakan bahwa kediktatoran militer “menimbulkan tragedi yang paling buruk dan paling kejam” dalam sejarah negara itu. Namun, pendahuluan itu juga menyatakan bahwa “pastilah ada hal-hal yang bisa didapatkan dari bencana-bencana yang buruk”. Sejarah penderitaan ini dianggap memberikan pelajaran. “Tragedi yang diawali dengan naiknya kediktatoran militer pada bulan Maret 1976, tragedi terburuk yang pernah dialami negara kita, tidak dapat diragukan lagi akan dapat membantu kita untuk memahamai bahwa hanya demokrasi-lah yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kesengsaraan pada skala ini”.148 Menurut laporan ini, pengetahuan tentang penderitaan memainkan peran penting dalam kemampuan negara untuk melakukan transisi politik ke demokrasi. Narasi dalam laporan transisi lainnya mengikuti alur yang serupa. Konfrontasi dengan masa lalu dianggap sebagai hal yang diperlukan bagi masyarakat yang hendak melakukan transisi menuju demokrasi. Laporan Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili menyatakan bahwa pertanggungjawaban sejarah merupakan syarat bagi tercapainya rekonsiliasi. Pengungkapan dan pengetahuan tentang penderitaan dianggap merupakan faktor utama yang mempersatukan negara. Keputusan pembentukan komisi kebenaran Cili menyatakan bahwa “kebenaran harus diungkapkan, karena hanya pada dasar demikian ... akan dimungkinkan ... terciptanya kondisi yang diperlukan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional sepenuhnya”.149 Menurut laporan Cili, kebenaran merupakan prasyarat utama untuk terciptanya demokrasi. Ini juga merupakan latar belakang dari laporan komisi kebenaran El Salvador. Ia muncul bahkan sejak judul laporan yang optimistik: From Madness to Hope, yang mengisahkan perang saudara yang penuh kekerasan, yang diikuti “kebenaran dan rekonsiliasi”. Menurut pengantar laporan tersebut, “konsekuensi kreatif” dari kebenaran akan “menyelesaikan perbedaan politik dan sosial melalui kesepakatan alih-alih dengan tindak kekerasan”. “Perdamaian akan dibangun berdasarkan transparansi ... dan pengetahuan”. Kebenaran diibaratkan sebagai “cahaya terang” yang mencari pelajaran-pelajaran yang berguna bagi rekonsiliasi dan untuk menghapus tindakan-tindakan demikian dalam masyarakat yang baru”.150 Bahkan laporan-laporan tidak resmi juga memiliki klaim serupa bahwa pengungkapan kebenaran merupakan suatu bentuk keadilan. Bagian pendahuluan laporan Nunca Más Uruguay misalnya menyatakan bahwa penulisan laporan itu dengan sendirinya merupakan kemenangan terhadap penindasan. Pandangan ini memiliki beberapa klaim tentang kaitan pengetahuan sejarah dengan prospek demokratis. Ia mengklaim bahwa pengungkapan kebenaran pada saat transisional akan mencegah kemungkinan represi di masa depan. Adalah kurangnya “pemahaman kritis yang menimbulkan risiko terulangnya bencana di masa depan ... untuk menyelamatkan sejarah, perlu belajar dari pengalaman ... Kita perlu keberanian untuk tidak menyembunyikan pengalaman-pengalaman tersebut dalam kesadaran kita, dan mengenangnya. Dengan demikian kita tidak akan jatuh lagi ke dalam perangkap yang sama”.151 Dalam penyusunan sejarah transisional menuju pemerintahan yang liberal, kisah tentang sejarah haruslah diketahui sebenar-benarnya. Namun, kisah-kisah yang diceritakan Laporan CONADEP, 6. Supreme Decree No. 355, “Creation of the Commission on Truth and Reconciliation”, 25 April 1990, direproduksi dalam Laporan Rettig. 150 Laporan Komisi Kebenaran El Salvador, 11. 151 Uruguay, Nunca Más, vii, x-xi. 148 149 48 menunjukkan beberapa loncatan puitis. Apakah kebenaran mendorong perubahan politik menuju liberalisasi, atau perubahan politik yang memungkinkan kembalinya pemerintahan demokratis dan usaha pengungkapan kebenaran? Dan bagaimana tepatnya cara kebenaran mencegah bencana di masa depan? Klaim teoretis bahwa kebenaran dapat membebaskan – dan bahwa “kebenaran” memungkinkan pergeseran ke demokrasi – tampak tidak tepat di manapun. Pergeseran dari kediktatoran tidak tergantung pada kebenaran; bahkan pergeseran ke sistem pemilihan bebas dan sistem politik yang lebih terbuka biasanya mendahului proses pencarian kebenaran. Namun, meskipun terdapat perubahan politik, ada anggapan bahwa kebenaran tentang masa lalu yang mengerikan tidak dapat ditemukan hingga (sebelum) ada usaha untuk mengklarifikasi penipuan di masa lalu itu. Sebagai contoh, pada transisi pascakomunis, sejarah-sejarah nasional menggambarkan kejahatan sebagai sesuatu yang datang dari luar. Tinjauan-tinjauan diawali dengan kisah pendudukan dan perlawanan rakyat, dan berpuncak pada kolaborasi. Narasi transisional tentang kediktatoran dan penindasan diawali dengan representasi “musuh” sebagai suatu hal yang asing, tidak dikenal dan kemudian bergerak ke temuan tentang kolaborasi yang dilakukan beberapa warga negara, di seluruh bagian masyarakat. Dalam narasi transisi, baik dari pemerintahan totaliter di bekas blok Soviet atau dari pemerintahan militer otoriter, yang paling menonjol adalah tentang penemuan fakta tragis ini. Dengan pengisahan seperti ini, dampak paling menonjol dari pengungkapan pengetahuan adalah bahwa ia memungkinkan perubahan di masa mendatang, melalui potensi tindakan manusia. Pengetahuan yang terungkap menunjukkan bahwa ada logika tentang kejahatan di masa lalu, dan bahkan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyikapinya. Pandangannya adalah bahwa seandainya hal ini sudah diketahui sebelumnya, mungkin keburukan-keburukan itu tidak akan terjadi, dan sebaliknya, karena “kebenaran” telah terungkap, maka langkah ke depan akan menuju ke arah yang lebih baik. Harapan ini merupakan esensi liberalisme. Tinjauan transisional berupa pengetahuan, yang baru terungkap tentang masa lalu yang buruk adalah bentuk kebenaran yang membebaskan, yang memiliki potensi liberalisasi. Pengungkapan kemungkinan pilihan di masa mendatang inilah yang menjadi ciri transisi liberal. Dalam tinjauan transisional, termuat masa depan yang liberal. Dalam kisah-kisah yang dimuat dalam laporan, kebenaran yang diungkapkan membantu menciptakan pergeseran dari masa lalu yang tragis ke masa depan yang penuh harapan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kisah yang terjadi dan diceritakan ini adalah tentang bencana, yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti dalam narasi dramatik, satu nasib buruk dapat dihindari pada satu titik tertentu. Keadilan transisional memainkan peranan tersebut melalui masuknya orang-orang yang memiliki akses khusus terhadap pengetahuan, seperti hakim, komisioner, saksi dan korban. Mekanisme pembebasan dan koreksi memungkinkan pergeseran dalam kisah masyarakat ini dari bencana ke masa depan yang lebih baik. Pergeseran ke masyarakat yang lebih liberal ini dimungkinkan dengan menghadapi masa lalu: narasi transisional biasanya bersifat progresif dan romantik. Sering pula terdapat sedikit ironi di dalamnya, bentuk-bentuk defeatisme, keinginan untuk gagal, dan konservatisme. Ini terlihat dalam narasi Eropa Timur, di mana para subjek dalam proses transisi tidak dianggap penting: mereka yang ditindas (atau dicopot dari jabatannya) hanyalah berada di tempat atau waktu yang salah, sehingga mereka menjadi bagian dari proses hukum; mereka dipandang 49 sebagai korban,152 seperti dalam kasus pengadilan penjaga perbatasan yang berpangkat rendah di Jerman. Dalam tinjauan-tinjauan tersebut, proses transisi diungkapkan seterbuka mungkin, dan proses legal berisiko kehilangan legitimasinya. Bila narasinya akan menjadi perulangan sejarah, kejahatan negara yang berulang, masa-masa itu tidak akan menjadi masa transformatif, namun hanya sekadar transisi konservatif. Literatur tentang masa-masa kekejaman biasanya disusun dari kisah-kisah pengalaman, dalam struktur yang khas. Dalam berbagai kebudayaan politik, representasi dalam literatur penindasan negara memiliki bentuk yang amat literal. Bentuk ini terlihat dalam tulisan-tulisan tentang penindasan dalam Perang Dunia Kedua dan Holocaust, dan kebanyakan berupa pengalaman. Contoh penting misalnya Night karya Elie Wiesel.153 Horor dalam kamp konsentrasi dikisahkan secara “kering” dari sudut pandang orang pertama yang mengalaminya langsung. Satu contoh lain dalam bentuk film adalah Shoah, yang menggunakan simbolsimbol ekstrem untuk menggambarkan hal-hal yang nyaris tak terbayangkan. Ketegangan ini terungkap dalam bentuk hibrida yang disebut sebagai novelareal; sebuah ilustrasi tentang kediktatoran Argentina sebagaimana tertuang dalam karya berbahasa Spanyol dari Miguel Bonasso, Recuerdo de la Muerte. Suatu karya fiksi yang paling bisa menggambarkan represi pada era Stalin adalah The Gulag Archipelago, 1918-1956: An Experiment in Literary Investigation, oleh Aleksandr Solzhenitsyn.154 Dari judulnya, Literary Investigation, ia mencoba menggambarkan ribuan insiden kekerasan dalam satu narasi: struktur novel ini serupa dengan laporan resmi. Penggunaan model kronika untuk menggambarkan kekerasan ini tidak selalu diikuti, ada pula penggunaan puisi. Ketika puisi menggambarkan penderitaan massal, hal ini dilakukan dalam bentuk “laporan mokro”.155 Literatur transisi tentang masa lalu yang penuh penindasan, seperti juga laporan resmi yang dijelaskan di atas, memiliki struktur transisional yang serupa. Diawali sebagai tragedi dalam sejarah suatu negara, narasi dimulai dengan gambaran tentang ketidakteraturan politik atau ekonomi yang dianggap menjelaskan bagaimana militer mengambil alih kekuasaan. Narasi dilanjutkan dengan masa penderitaan yang diselubungi penindasan, yang berpuncak pada penemuan dan pengetahuan-diri, yang merupakan titik balik, yang memungkinkan perubahan di masa depan. Suatu contoh penting adalah Prisoner without a Name, Cell without a Number, yang merupakan otobiografi Jacobo Timerman berdasarkan pengalamannya selama represi militer Argentina. Dalam bukunya, Timerman mengisahkan kisah sedih tentang bagaimana ia, sebagai bagian elite Argentina, semula menyetujui pengambilalihan kekuasaan ini, karena berharap bahwa hal ini akan mengembalikan ketenteraman. Namun, militer malah menceburkan negara ke dalam pembantaian dan pada akhirnya bahkan mengejar-ngejar Timerman. Hanya setelah dikhianati dan menderita, Timerman menyadari betapa brutalnya kekejaman militer ini. Titik balik nasibnya ini membuat ia memahami lebih dalam nasib negaranya. Lihar René Girard, The Violence and the Sacred, Baltimore: Johs Hopkins University Press, 1972. Lihat umumnya Saul Friedlander (ed.), Probing the Limits of Representation, Cambridge: Harvard University Press, 1992. Lihat misalnya Elie Wiesel, Night (terjemahan Stella Rodway dan Francis Mauriac), Bantam Books, 1982. 154 Lihat Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago: An Experiment in Literary Investigation, New York: Harper and Row, 1975. Miguel Bonasso, Recuerdo de la Muerte, Buenos Aires: Plancta, 1984. Jacobo Timerman, Prisoner without a Name, Cell without a Number, New York: Knopf, 1981. 155 Czeslaw Milosz, The Witness of Poetry, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983. 152 153 50 Narasi transisional menunjukkan bahwa hal minimal yang dipertaruhkan dalam transformasi ke liberalisasi adalah perubahan interpretasi. Masyarakat mulai berubah secara politis bila terjadi perubahan pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Perubahan inilah, seperti dikatakan Václav Havel, “dari hidup dalam kebohongan ke hidup dalam kebenaran.” Demikianlah banyak karya fiksi tentang masa tersebut adalah kisah tentang perubahan ini, tentang hidup dalam kebohongan, kisah penipuan dan pengkhianatan, ke pengungkapan pengetahuan yang baru dan pemahaman yang mempengaruhi dan membentuk identitas dan hubungan yang baru. Contohnya adalah karya Bernhard Schlink, The Reader, yang merupakan alegori hubungan negara dengan warga negara.156 Sejarah transisional bukanlah semata-mata pencarian fakta dalam kondisi yang steril, namun dibangun di atas narasi-narasi nasional yang sudah ada. Mereka tidaklah bersifat mendasar, namun lebih transisional, sebagai perubahan rezim kebenaran yang dikonstruksikan dalam perubahan rezim politik. Ketika terdapat interpretasi yang beragam tentang represi pemerintahan dalam suatu rezim politik, keberadaan interpretasi yang berbeda ini menandakan perubahan politik, yang mendorong perubahan lebih lanjut. Pemahaman fungsi interpretif dalam perubahan politik menjelaskan bahwa usaha untuk mendapatkan pertanggungjawaban historis tidak semata-mata merespon perubahan politik. Namun, pertanggungjawaban historis itu merupakan bagian dari penciptaan perubahan politik, yang menyusun apa yang kita harapkan dari sistem politik liberal. Tinjauan transisional yang dibahas di atas menunjukkan kontinuitas keadilan historis dan keadilan transisional lainnya. Konsepsi keadilan yang dibahas di sini menunjukkan alur yang serupa berkaitan dengan peran pengetahuan yang terungkap. Tinjauan sejarah menciptakan kaitan normatif dalam mengaitkan masa lalu dan masa depan suatu masyarakat; narasi transisi dimulai dengan melihat ke belakang dan bercermin pada arti masa lalu, namun selalu dengan tujuan untuk masa depan. Selalu ada yang bisa dilakukan. Ini adalah harapan yang diberikan oleh proses liberalisasi. Seperti respon-respon legal yang dibahas dimuka, seperti penghukuman, keserupaannya terletak pada tujuan korektif melalui proses legal. Artinya, dengan menciptakan perubahan pengetahuan sosial, terjadi pergeseran yang berarti dari kejahatan dan penderitaan di masa lalu ke masa depan yang menyembuhkan. Tentang Penyeberangan Sungai dan Laut, tentang Pembuangan dan Kepulangan Tinjauan-tinjauan di atas menunjukkan struktur dan ciri serupa pada transisi masyarakat. Struktur tersebut juga terlihat dalam karya-karya sastra klasik yang dikaitkan dengan transisi; yaitu bahwa mereka menunjukkan konvensi pergeseran dari tragedi ke komedi-romantik. Yang menjadi harapan akhir adalah kemungkinan rekonsiliasi. Kisah dalam Alkitab tentang dua saudara, Esau dan Yakub, merupakan kisah klasik tentang konfrontasi dengan masa lalu yang buruk, rekonsiliasi dan perubahan politis.157 Dalam kisah transisi biblikal ini, penyelesaian “hutang” antara kedua saudara ini terjadi setelah kembalinya Yakub, yang telah melarikan diri dan terasing dari saudaranya, Esau. Hubungan Havel, Power of the Powerless. Bernhard Schlink, The Reader (terjemahan Carol Brown Janeway), N.Y: Vintage Int’1, 1998. 157 Lihat W. Gunther Plaut (ed.), “Genesis” dalam The Torah: A Modern Commentary, New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981, Kejadian 32:4-17. 156 51 mereka yang buruk sejak awal mula berkaitan dengan persaingan tentang hak kesulungan dan penipuan Yakub terhadap Esau. Ketika Yakub merencanakan kepulangannya, ia takut untuk bertemu dengan saudaranya, takut bahwa Esau akan membalasnya.158 Ketika diberitahu bahwa Esau sedang pergi mendatanginya dengan sekelompok orang bersenjata, Yakub berusaha untuk menenangkan saudaranya dengan hadiah-hadiah, namun kemudian mengalami transformasi pribadi yang pada akhirnya mengarah pada rekonsiliasi dengan saudaranya dan pembangunan sebuah bangsa. Kisah pertemuan dan rekonsiliasi kedua saudara ini diawali dengan Yakub meninggalkan tempat pengasingannya. Setelah menyeberangi sungai Yabok pada malam hari, ia terlibat perkelahian dengan seorang asing yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketika berkelahi tersebut, kakinya terkilir sehingga jalannya pincang. Dan, ketika pertandingan gulat itu berakhir, ia diberkati dan mendapatkan nama baru: dari “Yakub” menjadi “Israel”, dan identitas baru yang disimbolkan nama itu menunjukkan pergulatannya dengan Tuhan. Setelah perkelahian tersebut, ketika ia dengan terpicang-pincang mendatangi saudaranya dan mendekatinya dengan penuh permohonan, ia mengalami transformasi baik jiwa maupun raga. Ketika saudaranya Esau melihatnya mendatanginya, mereka saling berpelukan dan menangis, dan terjadilah rekonsiliasi. Kisah kuno tentang rekonsiliasi ini diawali dengan penyeberangan suatu sungai, diikuti oleh malam pergulatan, pertemuan dengan kekuatan yang amat besar, dan perubahan identitas. Hanya setelah Yakub selesai dengan pergulatan ini, yang disimbolkan oleh kehilangan – ia menjadi pincang – dan mendapatkan nama baru, rekonsiliasi dengan saudaranya bisa terlaksana. Perlu diperhatikan bahwa meskipun Esau datang dengan marah bersama orangorang bersenjata, setelah menghadapi Yakub yang telah berubah, seorang baru bernama Israel, mereka berdamai. Apa yang menjadi syarat transisi? Kisah kuno ini menunjukkan simbol-simbol utama: penyeberangan sungai Yabok di malam hari – suatu penyeberangan dalam aspek tempat dan waktu. Malam hari melambangkan waktu yang membatasi (antara dua hari), waktu untuk menyusun kembali seseorang, dan air merupakan simbol klasik sesuatu perubahan.159 Setelah air dan malam hari, masih ada kehilangan dan sesuatu yang didapatkan. Dalam kisah biblikal perubahan Yakub menjadi Israel, transformasi identitas politis ini terlihat di tubuh (yang menjadi pincang) dan tercermin dengan perubahan nama. Struktur khas dari narasi transisional ini tergambar jelas dalam karya romantik, seperti The Tempest karya William Shakespeare. Seperti kisah Esau dan Yakub, The Tempest juga merupakan narasi transisi melalui pengasingan dan kepulangan. Diawali dengan para tokohnya dalam pengasingan dan berakhir dengan kepulangan mereka, mereka semula diasingkan dari rumah; secara harfiah “berada di laut”. The Tempest, seperti kisah biblikal di muka, diawali dengan pengisahan suatu ketidakadilan politik. Seperti antara Yakub dan Esau, terdapat permusuhan antara Prospero, penguasa “sah” Milan, dengan Antonio, yang menyerobot kekuasaannya. Kisah ini bercerita tentang persaingan mereka untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat yang sedang runtuh. Transisi ke kondisi politik yang baru, seperti 158 “Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya ... .” Kejadian 32:11. 159 Lihat Arnold Van Gennep, The Rites of Passage (terjemahan Monika B. Wizedom dan Gabrielle L. Caffee), Chicago: University of Chicago Press, 1960. 52 dalam kisah biblikal di muka, juga berupa narasi kepulangan dari pengasingan ke rumah. Perubahan ini tergantung pada pengungkapan berbagai kebenaran sehingga para tokoh akhirnya bisa pulang ke “kondisi asal”. “Dan Ferdinand saudaranya mendapatkan seorang isteri ketika ia tersesat; Prospero kekuasaannya di sebuah pulau terpencil; dan kita mendapatkan diri kita sendiri, ketika tidak seorang pun memiliki dirinya”.160 Drama ini diawali pada babak I dengan tokoh-tokohnya menceritakan ketidakadilanketidakadilan politik di masa lalu: Prospero kehilangan kekuasaannya, Ariel tertangkap dan kemudian diperbudak Prospero. Pada babak II, mulai dibayangi alternatif terhadap rezim yang ada. Pergeseran dimulai pada babak III, dengan mulainya para tokoh menghadapi sejarah. Konfrontasi terjadi melalui kekuatan supranatural (Ariel sebagai “monster”), yang menuntut “tiga orang berdosa” dan mengutuk mereka untuk kehancuran pelan-pelan”.161 Dengan terungkapnya kebenaran, dalam babak IV, mulai terbayang keinginan untuk perubahan dan pembalasan.162 Dalam babak V, sejarah dihadapi, pengampunan dan maaf menjadi pemikiran. “Kebesaran hati adalah nilai yang lebih berharga daripada pembalasan”.163 Rekonsiliasi berarti Prospero memberikan pengampunan dalam penggunaan kekuasaannya lebih lanjut. Bahwa peristiwa-peristiwa yang menyusul melibatkan pilihan manusia untuk menyikapi kondisi, untuk mendamaikan cinta dengan realitas, disimbolkan oleh permainan di dalam drama: permainan catur antara Ferdinand dan Miranda – simbol adanya kemungkinan dalam pikiran rasional dan tindakan individual. Pada akhir drama, hampir semua hal kembali ke keadaan semula, dan ketidakadilan diselesaikan. Dalam The Tempest, transisi ke rezim baru juga mengakibatkan kehilangan. Sementara dalam The Tempest kedua saudara tersebut tidak sepenuhnya berdamai, terjadi rekonsiliasi antara tokoh-tokoh lainnya. Bahkan, melalui drama ini dapat dipahami bahwa transisi berarti penciptaan interpretasi baru yang menggantikan interpretasi lama. Perubahan yang menjadi inti transisi memerlukan hilangnya sesuatu, sekaligus perubahan identitas.164 Narasi transisional memiliki bentuk yang khas. Baik dalam kisah biblikal maupun roman Shakespeare ini, alur narasi bergeser dari pembuangan ke rumah, ke kondisi semula yang sebenarnya. Pengungkapan kebenaran sering kali terjadi melalui proses supranatural; secara ritual melepaskan diri dari masa lalu, membuang masa lalu dan akhirnya mengakui kebenaran yang baru, memungkinkan kembali ke arah yang benar. Pengetahuan yang semula dirahasiakan dihadapi, dan akhirnya menciptakan arah yang baru.165 Pengetahuan suatu masyarakat tentang apa yang telah terjadi bukanlah sasaran akhir, namun syarat untuk terjadinya perubahan sikap manusia dan transformasi ke liberalisme. Keadilan Historis Transisional: Beberapa Kesimpulan Lihat The Tempest 5.1.211-14. Lihat ibid., 3.3.52-77. 162 Lihat ibid., 4.1. 163 Ibid., 5.1.27-32. 164 Lihat Stanley Cavell, Disowning Knowledge in Six Plays of Shakespeare, Cambridge: Harvard University Press, 1987. 165 Lihat Jürgen Habermas, A Berlin Republic: Writings on Germany (terjemahan Stevan Rendall), Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. 160 161 53 Praktik-praktik yang dibicarakan di sini menunjukan bahwa peran penyelidikan sejarah bukanlah sebagai dasar, namun sebagai cara transisi. Sejarah selalu terkait erat dengan kehidupan bernegara, namun dalam pergeseran politik, ia membantu mendorong transformasi. Dibandingkan dengan sejarah versi negara yang sedang berjalan, apa yang menjadi ciri utama narasi sejarah transformatif? Apa yang menjadikan kisah-kisah tersebut membawa pembebasan? Satu alasan mengapa sejarah yang dibicarakan di sini tidak bersifat mendasar namun bersifat transisional adalah bahwa ia merupakan sejarah yang khas dan terpisah (discrete), narasi “mini” dan bukan metanarasi, yang berada di dalam narasi luas negara. Pengungkapan sejarah transisional bukanlah narasi yang berdiri sendiri, juga bukan awal baru yang radikal, namun selalu berkaitan dengan peninggalan sejarah suatu negara yang sudah ada. Sejarah transisional memerlukan negosiasi antara berbagai versi sejarah yang berbeda-beda, dan ditempatkan dalam narasi sejarah negara yang lebih luas. Tinjauan transisional diciptakan dalam suatu konteks – sejarah suatu negara – dan merupakan respon kritis terhadap konflik sejarah yang ada. Maka, sejarah transisional pada umumnya menunjukkan penggantian satu versi interpretasi sejarah, atau suatu rezim kebenaran, dengan rezim kebenaran lainnya, sementara rezim politik berganti namun mempertahankan benang merah narasi negara. Proses hukum pengungkapan kebenaran mengkonstruksi ingatan kolektif dalam transisi. Penggunaan hukum, proses dan kerangkanya secara terbuka ini dilakukan pada saat konsensus sosial sedang dalam kondisi berantakan. Hukum merupakan suatu bahasa tegas dengan simbol-simbol dan ritus-ritus yang sudah mapan. Pada masa kontemporer, ritus legal dan proses pengadilan serta dengar pendapat terbuka memungkinkan terciptanya sejarah transisional yang merupakan konstruksi sosial bersifat demokratis dengan cakupan yang luas; pemirsanya adalah seluruh warga negara. Ritus-ritus penyusunan sejarah kolektif ini merupakan bagian dari transisi dan menciptakan batasan waktu politik: “sebelum” dan “sesudah”.166 Penggunaan hukum berarti bahwa klaim sejarah dilakukan dengan menggunakan bahasa hukum, berkaitan dengan hak dan tanggung jawab terhadap kesalahan di masa lalu. Penggunaan bahasa ini merupakan respon kritis untuk menjawab penindasan masa lalu, meninggalkan fakta-fakta khas dan terpisah yang semula digunakan untuk mendukung rezim lama, yang merupakan hal kritis untuk memungkinkan perubahan politik. Praktik penciptaan sejarah yang dikaitkan dengan transisi ini sering kali secara terbuka menegaskan apa yang secara tersirat sudah diketahui oleh masyarakat. Proses penyelidikan sejarah memungkinkan terlepasnya sejarah masa lalu yang jahat dari ingatan masyarakat. Narasi sejarah transisional mengisahkan keadilan korektif yang menunjukkan diskontinuitas dari masa lalu; sejarah transisional mengarah pada liberalisasi. Narasi sejarah transisional, baik melalui pengadilan maupun bentuk lainnya, menunjukkan peran penting pengetahuan dan pilihan. Melalui pengetahuan umum tentang respon historis terhadap pelanggaran di masa lalu, di mana sebab dan akibat struktural dapat dipahami,167 sejarah transisional berupa narasi yang jelas dapat menjelaskan tanggung jawab individu dan kolektif. Dengan memberikan potensi pilihan individual, tinjauan sejarah memainkan peran liberalisasi. Dengan mengungkapkan kebenaran masa lalu, tinjauan tersebut menunjukkan hal-hal apa yang mungkin berubah seandainya telah diketahui sejak awal, Lihat Maurice Bloch, Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology, London: Athlone Press, 1989, 282 (tentang peran ritual dalam konstruksi). 167 Lihat Gordon, “Undoing Historical Injustice”. 166 54 berkaitan dengan potensi tindakan individual. Inilah pemahaman yang dijelaskan oleh tatanan politik tentang penghindaran tragedi. Pengungkapan potensi pilihan dan tindakan individual dengan sendirinya merupakan suatu hal yang meliberalkan. Peninjauan sejarah merupakan ciri transisi menuju liberalisasi, berkaitan dengan perubahan identitas politik negara. Dengan demikian narasi transisional memajukan konstruksi tatanan politik kontemporer. Dalam narasi transisional, alur cerita tidak semata-mata tragis atau mempermasalahkan penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang. Ia tidak menaati tatanan dunia yang sudah ada atau pada realisme politik semata-mata. Narasi-terstruktur menekankan kemungkinan pilihan yang terbatas, oleh agen-egen individual dalam politik yang terletak dalam parameter kondisi politik yang lebih luas. Terdapat anggapan bahwa pemahaman diri di tingkat masyarakat dapat memberikan penebusan kesalahan, meskipun di masa lalu terjadi kesalahan, yang merupakan pemahaman yang sangat liberal. Narasi sejarah yang menekankan pemahaman diri di tingkat masyarakat dan mencegah pengulangan tragedi dikaitkan dengan tatanan politik liberal. Struktur sejarah transisional menunjukkan adanya harapan. Liberalisasi melalui pengisahan kebenaran menyebabkan instabilitas, yang dikaitkan dengan masa transisi. Namun yang membahayakan adalah pengisahan yang terlalu baik, yang terlalu merasionalisasi – menganggap bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk masa depan yang liberal. Bagaimana sejarah dikisahkan seiring perjalanan waktu merupakan hal yang sensitif. Narasi sejarah mengkonstruksikan pemahaman negara terhadap tatanan politiknya. Keadilan historis transisional terkait dengan pemeliharaan identitas politik suatu negara. Dengan berjalannya waktu, bagaimana suatu negara memahami dirinya menadi subjek kontroversi perdebatan politik. “Perdebatan sejarawan” yang memunculkan kembali pertimbangan-pertimbangan transisional menunjukkan bahwa bila narasi suatu negara secara eksplisit diskontinu dengan peninggalan sejarah penindasan di masa lalu, ia menekankan identitas transisional yang meliberalkan. Praktik-praktik sejarah yang dibicarakan di atas menunjukkan bahwa semua respon legal menciptakan narasi transisional. Meskipun narasi tersebut tidak selalu eksplisit, namun akan selalu tercipta suatu tinjauan sejarah. Praktik transisional penyusunan sejarah dalam masa perubahan politik radikal menjelaskan peran narasi sejarah sebagai latar belakang dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, tinjauan sejarah yang menjadi dasar tatanan politik.168 Suatau genre sejarah yang khas kini diasosiasikan dengan identitas politik liberal. Seperti dibicarakan di sini, ada beberapa ciri umum dari narasi sejarah liberal ini. Sejarah transisional juga terkait erat dengan konteks dan kondisi politik. Bila sejarah dipergunakan untuk melayani perubahan poitik, tujuannya prospektif, dan historiografi modern menegaskan bahwa penulisan sejarah tidak bisa dilepaskan dari politisasi. Namun, parameter diskursus sejarah ditempatkan dalam konteks sosial yang ada. Penyusunan sejarah transisional ditempatkan dalam konteks tinjauan-tinjauan yang sudah ada, dan ketika mereka menggantikannya, hasil penyusunan yang baru itu menjadi versi sejarah yang diterima (yang di masa berikutnya bisa digantikan oleh versi lainnya). Sejarah transisional menjadi mekanisme kontinuitas sekaligus diskontinuitas. Siklus pergantian rezim kebenaran tampak dalam respon sejarah terhadap kejahatan di masa lalu. Dan lebih lanjut lagi, hal yang Untuk pemikiran yang mendalam, lihat Robert Gordon, “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review 36 (1984): 57. 168 55 menimbulkan diskontinuitas dari rezim yang sudah ada tidaklah penting dan tergantung pada politik. Sejauh mana siklus ini berlanjut? Apa kaitan antara penyusunan sejarah transisional dan non-transisional? Sering kali terdapat harapan untuk menyusun suatu versi final dari sejarah – konsensus sejarah yang mutlak – yang diharapkan “melampaui sejarah”. Hal ini sama sekali tidak benar bahkan setelah gelombang terakhir perubahan menyusul keruntuhan komunisme. Namun, dorongan untuk menamatkan sisa-sisa masa lalu, menegakkan sosok “pasca-sejarah” ini merupakan hal yang sia-sia, karena tidak mungkin menghentikan peninjauan sejarah suatu negara, untuk menghentikan politik dan potensinya untuk kemajuan. Usaha untuk menetapkan suatu versi sejarah berdasar pandangan tertentu untuk selamalamanya merupakan pandangan yang iliberal. Tidak ada pilihan lain, selain pluralitas narasi, instabilitas dan dialektika politik. 56 Bab 4 Keadilan Reparatoris Pada masa kontemporer, hampir semua rezim transisional – baik setelah terjadinya perang, kediktatoran militer maupun komunisme – mengambil langkah berupa keadilan reparatoris. Tinjauan praktik reparatoris yang dibahas di sini menunjukkan bahwa respon ini tersebar luas dalam berbagai budaya hukum yang berbeda. Bagaimana masyarakat menganggap tindakan-tindakan reparatoris tersebut? Apa kegunaan dan fungsinya? Apa arti keadilan transisional bagi para korban kejahatan rezim lama dan bagi masyarakat? Dilema yang dihadapi rezim penerus dalam masa-masa transisi adalah apakah rezim yang baru memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian bagi para korban kejahatan negara. Menurut hukum internasional, bila negara melanggar kewajibannya, terdapat kewajiban hukum yang jelas untuk memberi ganti kerugian.1 Namun, dalam perdebatan nasional tentang apa yang harus dilakukan untuk menyikapi peninggalanpeninggalan kejahatan dari masa lalu, pertanyaan tentang keadilan reparatoris menjadi masalah yang lebih kompleks yang diwariskan kepada rezim penerus. Ia menimbulkan konflik antara tujuan pemberian kompensasi bagi para korban pelanggaran negara yang memandang ke belakang, dan kepentingan politik negara yang memandang ke depan. Praktik reparatoris menimbulkan dilema-dilema, prospektif-retrospektif dan individualkolektif yang mencirikan masa transisi. Namun, baik pada masa biasa atau transisi, keadilan reparatoris selalu bersifat memandang ke belakang, karena ia merujuk pada perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Keadilan reparatoris transisional, seperti akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini, mendamaikan dilema tersebut dalam konteks perimbangan antara tujuan korektif dan sasaran transformasi yang memandang ke depan. Demikian pula, keadilan reparatoris transisional menengahi masalah tanggung jawab individu dan kolektif, dan membentuk identitas politik negara yang sedang menuju liberalisasi. Istilah “keadilan reparatoris” memiliki dimensi yang luas, yang mencakup berbagai bentuk berbeda: pemulihan (reparation), ganti rugi material, pengembalian nama baik, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan pemberian tanda mata. Presedenpreseden terhadap hal ini telah ada sejak zaman kuno, dan menggambarkan peran kompleks keadilan reparatoris transisional. Respon reparatoris transisional menengahi penyembuhan luka korban dan komunitas, masa lalu dan masa kini, dan meletakkan dasar untuk kebijakan redistribusi yang dikaitkan dengan pergolakan radikal. Reparasi dalam Alkitab: Keluaran (Eksodus) dari Mesir 1 PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sesi ke-45, Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms: Final Report, disiapkan oleh Theodorr Van Boven, 2 Juli 1993, U.N. doc. E/CN.4/suh.2/ 1993/ 8; Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford: Clarendon Press, 1989, 171, n24, 1989; Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford: Clarendon Press, 1989. 1 Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang buka kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. (Kejadian 15: 13-14) Kisah dalam Alkitab tentang pergeseran politik – dari penindasan ke kebebasan – umat Israel di Mesir merupakan suatu kisah klasik tentang transisi. Menurut kisah tersebut, orang-orang Israel tinggal di Mesir selama sekitar empat ratus tahun, diperbudak dan dianiaya. Tahun-tahun perbudakan ini diikuti oleh kebebasan dari Mesir, hukuman diberikan kepada orang-orang Mesir dan akhirnya terbentuklah negara Israel. Kisah Keluaran dan penghukuman orang Mesir sudah terkenal, namun tidak banyak yang diketahui tentang pemberian reparasi yang berkaitan dengan Keluaran ini. Kisah ini menunjukkan misteri dan ambiguitas berkaitan dengan praktik reparatoris pada masa perubahan politik. Dalam kisah ini, pada malam keluarnya warga Israel dari tanah Mesir, orangorang Israel, “meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain”.2 Tuhan memberitahu orang-orang Israel untuk mengambil barang-barang berharga dari orang-orang Mesir: “Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu”.3 Teks ini memberikan kesan bahwa barang-barang berharga ini sebenarnya bukan dirampas, namun diberikan dengan murah hati. Namun, teks ini memang terbuka untuk interpretasi yang berbeda, karena ada rujukan tentang “meminta” namun ada pula “merampasi orang Mesir”. Satu aspek lain dalam peristiwa pada malam itu terlihat dalam bagian lain yang mengelaborasi “perampasan” terhadap orang-orang Mesir ini: “Tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barangbarang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan; demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu”.4 Kisah ini menunjukkan bahwa ada pertukaran pakaian antara orang-orang Mesir dan Israel. Para budak yang dibebaskan ini mengenakan pakaian para tuan-tuan mereka, dan membiarkan mereka telanjang – seperti budak. Urutan ini menunjukkan akar dari kata redress. Berdasarkan akar katanya, ia berkaitan dengan pakaian yang dikenakan dalam upacara keagamaan yang menentukan status sosial. Dalam penggunaannya yang paling awal, pada Abad Pertengahan, redress mengaitkan pakaian dengan status dan kembalinya harga diri. Perampasan (pakaian) orang-orang Mesir yang kemudian dikenakan orang-orang Israel menunjukkan lebih dari sekadar pemberian ganti rugi material, hal ini adalah pelurusan sejarah, suatu upacara kompensasi, rehabilitasi di mata publik. Aspek simbolis kuno dari tindakan reparatoris ini terdapat pula dalam preseden-preseden berikutnya sepanjang sejarah. Apa arti sebenarnya dari reparasi era Keluaran ini? Kutipan dari Kitab Suci mendukung beberapa pemahaman yang berbeda. Pengambilan barang-barang emas dan 2 W. Gunther Plaut (ed.), “Exodus,” dalam The Torah: A Modern Commentary, New York: Union of American Hebrew Congregations, 1981, Ibid., 12:35. 3 Ibid., 12:35, 36. 4 Ibid., 3:21-22. 2 perak bisa dianggap sebagap pemberian hadiah, pinjaman, sogokan agar mereka pergi, pertukaran hak milik antara dua pihak, misalnya pertukaran barang-barang bergerak milik orang Mesir dengan tanah-tanah yang dimiliki orang Israel yang ditinggal, kompensasi untuk upah yang belum terbayar dan pelanggaran-pelanggaran lain yang terkait dengan perbudakan, atau sebagai ganti rugi simbolis, rehabilitasi status politik. Dalam satu interpretasi, kisah ini menjelaskan bagaimana orang-orang Israel memanfaatkan kondisi politik yang kacau dan menjarah barang-barang rampasan. Dalam interpretasi lainnya, ini bukanlah penjarahan oleh budak-budak yang kabur, namun pelaksanaan suatu rencana yang suci. Orang-orang Mesir memberikan emas dan perak tersebut sebagai reparasi dalam rangka keadilan yang diberikan oleh Tuhan.5 Interpretasi ini dibangun pada dasar rujukan lebih awal tentang orang-orang Israel itu menjadi “bangsa yang besar”, yang meramalkan klaim atas harta milik orang-orang Mesir. Bagaimana memahami kisah tersebut? Apakah perampasan dari orang-orang Mesir ini merupakan tindakan yang memandang ke belakang: barang-barang emas dan perak tersebut diambil untuk mengganti perbudakan dan penganiayaan di masa lalu? Atau apakah kisah tentang anak-anak Israel yang mengenakan pakaian orang Mesir bermakna memandang ke depan: barang-barang tersebut diambil untuk menjadi modal pembangunan suatu bangsa? Bahasa yang digunakan dalam teks-teks Kitab Suci ini mendukung kedua pandangan tersebut. Jika tinjauan biblikal tentang Keluaran diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan politis, konteks interpretatif tersebut adalah hermeneutika yang khas pada transisi, termasuk perbudakan selama bertahun-tahun sebelum malam Keluaran dan kelanjutannya dalam sejarah dari perbudakan menjadi negara yang besar. Konteks transisional ini memiliki aspek-aspek yang memandang ke belakang maupun ke depan yang mewarnai interpretasi praktik reparatoris. Seperti akan kita lihat, kisah ini masih memiliki gema, karena ia menggambarkan kualitas keadilan reparatoris yang memiliki banyak paradigma. Reparasi Pasca-Perang dan Kesalahan Perang Keseluruhan Pada akhir Perang Dunia Pertama, tuntutan agar Jerman memberikan reparasi menimbulkan pertanyaan tentang arti keadilan reparatoris. Di Versailles, tanggung jawab terhadap terjadinya perang dibebankan secara sepenuhnya kepada Jerman: kesepakatan damai membebankan tanggung jawab “seluruh kesalahan perang” kepada Jerman dan memaksanya untuk membayar reparasi dalam jumlah yang besar.6 Dalam kesepakatan 5 Lihat Nehama Leibowitz, Studies in Shemot: The Book of Exodus, terjemahan Aryeh Newman, Yerusalem: World Zionist Organization, Department for Torah Education and Culture in the Diaspora, 1976, 185. 6 Kewajiban Jerman untuk mengganti rugi pelanggaran-pelanggarannya ditetapkan dalam “Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal 3 Konvensi tersebut menyatakan: “Pihak dalam perang yang melanggar pasal-pasal dalam peraturan ini akan, bila diperlukan, harus bertanggungjawab untuk membayarkan kompensasi. Ia harus bertanggung-jawab untuk semua tindakan yang dilakukan orang-orang yang merupakan bagian angkatan perangnya”. “Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat”, pasal 3 (mulai berlaku 26 Januari 1910), U.S.T.S. 539 (memberikan kewajiban untuk membayar ganti rugi). Lihat Pasal 41 Konvensi Den Haag IV (memberikan hak untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang disebabkan pelanggaran); keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (mewajibkan tanggung jawab untuk pelanggaran berat. Pasal 68 Konvensi Jenewa berkaitan dengan Perlakuan terhadap Tawanan Perang, memberikan hak untuk mengklaim bagi para tawanan perang. 3 damai ini, ganti rugi yang dituntut dari Jerman bersifat punitif namun dijustifikasi sebagai pencegahan – melumpuhkan Jerman sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu lagi berperang. Traktat Versailles membebankan tanggung jawab kesalahan “perang agresif” pada negara Jerman. Traktat tersebut memahami tanggung jawab sebagai suatu hal yang bersifat kolektif, demikian pula dampak sanksi juga akan terasakan oleh seluruh negara. Setelah empat tahun berperang, Sekutu merasa berhak menuntut ganti rugi biaya perang, namun klaim untuk mendapatkan reparasi itu diberikan bukan sebagai tuntutan atas “hak” Sekutu, namun “kewajiban” Jerman. Klausul “kesalahan perang” dalam traktat Versailles ini menekankan liabilitas atau kewajiban-hukum Jerman secara keseluruhan, memaksa Jerman untuk bertanggungjawab atas “semua kerugian dan kerusakan pihak Sekutu ... sebagai konsekuensi perang yang dipaksakan terhadap mereka sebagai akibat ... agresi.” Pasal 231 Traktat Versailles menyatakan: “Pemerintah Sekutu dan negara-negara terkait menegaskan, dan Jerman menerima, tanggung jawab Jerman dan sekutu-sekutunya karena telah menimbulkan semua kerugian dan kerusakan pihak Sekutu dan negara-negara terkait beserta warga negaranya, sebagai konsekuensi perang yang dipaksakan terhadap mereka, sebagai akibat tindakan Jerman dan sektutu-sekutunya yang melakukan agresi.”7 Menurut klausul kesalahan perang ini, seluruh tanggung jawab terhadap terjadinya perang – semua biayanya – akan ditanggung oleh Jerman. Beban reparatoris yang amat berat dari Versailles menimbulkan beberapa pertanyaan. Timbul masalah praktis dari sanksi yang sedemikian berat yang menyebabkan Jerman hampir tidak mungkin membayarnya, seperti disadari waktu itu.8 Demikian pula masalah yang ditimbulkan dari sifat sanksi ekonomi yang tidak pandang bulu. Sifat tidak pandang bulu ini menyebabkan dampaknya dialami oleh semua unsur negara secara keseluruhan. Besarnya tuntutan reparasi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang sifat dan fungsinya: sejauh mana respon ini ditujukan untuk memberikan kompensasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan perang? Sejauh mana ia bersifrat punitif? Formulasi provisi reparasi dalam traktat Versailles memang ambigu, menunjukkan tujuan yang berganda. Traktat pasca-perang ini secara cerdik memisahkan pertanyaan tanggung jawab dari kewajiban hukum: kesalahan perang keseluruhan dibebankan atas dasar tanggung jawab pidana dan perdata; sementara reparasi tampaknya bersifat perdata, klausul “seluruh kesalahan perang” dalam Traktat Versailles ini secara eksplisit membedakan tanggung jawab dari pelaksanaannya, yaitu penerapan keputusan. Meskipun Pasal 231 menyatakan pertanggungjawaban keseluruhan Konvensi (No. IV) berkaitan dengan perlindungan terhadap Warga Sipil dalam Keadaan Perang (mulai berlaku 21 Oktober 1950), 6 U.S.T.S. 3114. Prorokol I (“Protokol Tambahan untuk Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan berkaitan dengan Perlindungan terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional”) (mulai berlaku 7 Desember 1978) dalam Pasal 91 menyatakan bahwa pihak yang melanggar pasal dalam konvensi “harus bertanggung-jawab untuk membayarkan kompensasi”, International Law Materials 16 (1977): 1392. Lihat Hugo Grotius, Rights of War and Peace: Including the Law of Nature and of Nations, Winnipeg, Can: Hyperion Press, 1979, 10. Lihat juga Percy Bordwell, The Law of War between Belligerents: A History and Commentary, Littleton, Colo: Fred B. Rothman, 1994. 7 Traktat Versailles, 28 Juni 1919, Pasal 231, bagian VIII, dalam Clive Parry (ed.), Consolidated Treaty Series, Vol 225 (1919). 8 Pasal 232 menyatakan: “Pemerintah Sekutu dan negara-negara terkait mengakui bahwa sumber-sumber daya Jerman tidak mencukupi, setelah memperhatikan pengurangan permanen sumber-sumber daya tersebut yang akan disebabkan oleh pasal-pasal lain dalam traktat ini, untuk memberikan reparasi sepenuhnya untuk semua kerugian dan kerusakan.” Ibid. 4 pada Pasal 231, Pasal 232 mengakui masalah kelangkaan sumber daya. Meskipun terdapat perdebatan substansial di pihak Sekutu tentang pertanyaan cakupan tanggung jawab hukum dan tingkat reparasi yang dituntut, bahasa yang digunakan dalam traktat menunjukkan terdapat pemahaman bahwa – lebih dari pembayaran untuk kerugian meterial – Jerman harus bertanggung-jawab secara moral, politis dan legal untuk terjadinya perang. Namun, traktat yang sama mengakui bahwa Jerman tidak akan (mampu) membayar. Kedua klausul aneh dalam traktat tersebut menandakan ambiguitas yang ditimbulkan praktik reparatoris pada masa transisi. Reparasi pasca-perang, seperti juga pada masa kuno, mencerminkan karakter gabungan dan kompleks dari sifat dan peran praktik-praktik tersebut. Praktik-praktik itu secara bersamaan memajukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada dan penghukuman kesalahan dari masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi masa lalu sekaligus memajukan sasaran politik yang luas dari transisi. Wiedergutmachung dan Schilumim Dari penyerahan tanpa syarat dan debu-debu kamp konsentrasi setelah Perang Dunia Kedua, timbullah proyek reparatoris terbesar dalam sejarah hingga kini, yang berjumlah puluhan milyar dollar selama setengah abad terakhir. Setelah perang ini, dua klaim reparatoris yang sangat berbeda dituntut kepada Jerman – satu dari musuh-musuhnya yang menang, dan yang lain dari para korbannya. Sejak awal proses perdamaian, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Sekutu menuntut Jerman untuk membayar ganti rugi karena melakukan perang secara tidak sah. Seperti dibicarakan di atas, setelah Perang Dunia Pertama, normanya adalah bahwa negara yang kalah membayarkan ganti rugi kepada pihak-pihak lainnya; skema reparasi jerman ini diciptakan berdasar program restitusi pasca-perang Dunia Pertama. Dalam transisi dari wilayah yang diduduki ke negara berdaulat, satu provisi penting dalam Traktat Transisional 1952 dengan kekuatankekuatan pendudukan adalah kewajiban untuk memberikan restitusi terhadap penyitaan hak milik yang terkait dengan perang selain kerugian-kerugian lainnya.9 Dorongan lain untuk reparasi datang dari para korban dan keluarga korban kampkamp pembantaian. Kisah tentang negosiasi yang mengarah pada kesepakatan reparasi antara Jerman, Israel dan kelompok-kelompok korban merupakan suatu kisah tentang dua kelompok yang mengalami transisi: yang pertama suatu negara yang kalah dengan perasaan kebangkrutan moral yang mendalam, yang satunya negara baru yang terdiri dari korban-korban penindasan dalam kebangkrutan fiskal. Setelah negosiasi panjang yang dipimpin Kanselir Jerman Konrad Adenauer menghasilkan kesepakatan Luksemburg pada tahun 1952, Jerman sepakat untuk memberikan sejumlah dana kepada organisasi yang mewakili korban-korban penganiayaan Nazi,10 dan juga reparasi kepada negara Israel yang baru terbentuk. Undang-Undang Kompensasi Federal ini memiliki lingkup 9 Lihat Republik Federal Jerman, Restitution, edisi bahasa Inggris, Bonn: Press and Information Office of the Federal Government, Juni 1988. 10 Untuk tinjauan tentang proses negosiasi, lihat Nana Sagi, German Reparations: A History of the Negotiations, Yerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1980. Lihat juga Frederick Honig, “The Reparations Agreement between Israel and the Federal Republic of Germany”, American Journal of International Law 48 (1954): 564. 5 yang luas dalam menanggapi korban-korban penindasan Nazi, memberikan kompensasi untuk cedera fisik dan kehilangan kebebasan, properti, pendapatan, pekerjaan atau kesempatan kemajuan keuangan yang disebabkan oleh penindasan atas alasan politik, sosial, religius atau ideologis.11 Pembayaran kepada para korban, wakil mereka dan negara Israel ini sebenarnya tidak dipengaruhi oleh hukum internasional masa itu, juga tidak ada preseden untuk tindakan tersebut. Analogi yang terdekat mungkin adalah pembayaran reparasi pascaperang tradisional, yang menurut hukum perang sejak Konvensi Den Haag 1907 merupakan kewajiban negara-negara yang melanggar norma-norma peperangan. Namun, pandangan ini mensyaratkan fiksi bahwa Jerman dan Israel adalah dua negara yang “bermusuhan”. Padahal, Israel bukan saja tidak berpartisipasi dalam perang, namun ia bahkan belum terbentuk. Pembayaran yang dijanjikan setelah kesepakatan 1952 oleh Republik Federal Jerman, seperti juga dalam masa kontemporer setelah unifikasi,12 berbeda dari pandangan tradisional tentang reparasi yang terkait perang sebagai hal yang bersifat nasional. Para penerima ganti rugi ini bukanlah negara yang menang, melainkan warga dari negara yang memberikan kompensasi tersebut. Mereka juga calon warga negara Israel, yang diwakili oleh negara penerima ganti rugi tersebut (Israel). Ini bukanlah reparasi pasca-perang seperti biasanya. Pembayaran pasca-Perang Dunia Kedua ini mengubah untuk selamanya konsep tentang reparasi. Setelah Nuremberg, perkembangan dramatis dalam hukum internasional memperluas norma-norma yang berkaitan dengan hukum perang melampaui lingkup internasional, dan memberlakukannya pada konflik internal dalam negara. Pada akhir perang, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 mendorong perkembangan hukum kemanusiaan internasional, dan mengusulkan reparasi terhadap pelanggaran hak-hak warga sipil dalam semua jenis konflik bersenjata.13 Kewajiban-kewajiban dalam hukum perang tentang reparasi bagi korban pelanggaran oleh negara lain mengarah pada kewajiban nasional untuk memberikan kompensasi bagi warga negara yang mengalami pelanggaran. Hasil yang bertentangan pun tampak: warga negara lain akan lebih dilindungi oleh hukum internasional daripada warga suatu negara dilindungi oleh sistem hukumnya sendiri, apabila ia mengalami pelanggaran hak. Munculnya kewajiban menurut hukum kemanusiaan internasional ini kemudian mendorong kewajiban reparatoris transisional bagi rezim penerus terhadap pelanggaran-pelanngaran negara di masa lalu. Standar reparatoris yang dikaitkan dengan hukum perang telah berkembang dan melampaui konteks konflik internasional ke konflik internal murni. 11 Lihat umumnya Republik Federal Jerman, Restitution. Lihat juga Kurt Schwerin, “German Compensation for Victims of Nazi Prosecution”, Northwestern University Law Review 67 (1972): 479. Untuk suatu pendekatan “Viktimologis”, lihat Lesslie Sebba, “The Reparations Agreements: A New Perspevtive”, Annals of the American Academy of Political and Social Science 450 (1980): 202. Untuk analisis kritis, lihat Christian Pross, Paying for the Past: The Strugle over Reparations for Surviving Victims of the Nazi Terror, Baltimore dan London: Johns Hopkins University Press, 1998. 12 Tentang perluasan kompensasi Jerman bagi orang-orang Yahudi di Timur yang menjadi korban penindasan Nazi, lihat David Binder, “Jews of Nazi Era Get Claims Details”, New York Times, 22 Desember 1992, rubrik internasional. 13 Ameur Zemmali, “Reparations for Victims of Violations of International Humanitarian Law”, dalam Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights Fundamental Freedoms, Maastricht: Netherlands Institute of Human Rights, 1992, 61-75. 6 Bagaimana kita memahami skema reparasi Jerman? Wiedergutmachung, istilah yang digunakan Jerman untuk reparasi tersebut, secara harfiah berarti “membuat jadi baik kembali”, atau mengembalikan ke kondisi semula.14 Dengan kegagalan denazifikasi, reparasi mendapatkan dukungan politis di Jerman sebagai cara untuk mendapatkan kembali kredibilitas dalam pandangan komunitas internasional. Sebaliknya, sebagai penolakan terhadap anggapan bahwa reparasi dapat membuat sesuatu menjadi “baik kembali”, kelompok-kelompok korban menyebut reparasi tersebut dengan istilah Ibrani Shilumim,15 yang berarti “melakukan pertobatan, membawa damai”. Bagi para korban, reparasi adalah masalah kebutuhan ekonomi, sehingga bagi mereka, titik awal negosiasi adalah biaya penempatan ulang para pengungsi. Bagi para pelaku dan korban, reparasi adalah persoalan penyelesaian masalah, namun dari cara yang berbeda bagi masingmasing. Namun, meskipun terdapat pemahaman yang amat berbeda tentang sifat dan tujuan skema reparasi, negosiasi konsep-konsep yang berbeda ini mencapai kesepakatan politik. Skema reparasi Jerman ini menjadi paradigma konsep reparasi transisional yang kompleks. Praktik reparatoris transisional dijustifikasi unsur-unsur pandangan ke belakang dan ke depan, moral, ekonomi dan politik. Mungkin tidak mengherankan bahwa reparasi pasca-perang dan reparasi yang merupakan hasil kesepakatan transisional, negosiasi politik dan kompromi, digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dan bahkan tampak bertentangan. Proyek reparatoris pasca-perang menunjukkan bahwa skema reparatoris transisional memilik tujuan ganda: memajukan kepentingan individual dan kolektif, korban dan masyarakat. Seperti akan kita lihat ketika meneliti berbagai praktik serupa dalam masa transformasi politik, fungsi ganda ini menunjukkan kekhasan skema reparatoris transisional. Perang Kotor, Penghilangan dan Rekonsiliasi: Peran Reparasi Penghilangan dan pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Velásquez-Rodríguez di Honduras pada dekade 1980-an menimbulkan reaksi berantai di seluruh Amerika Latin, mendorong timbulnya kebijakan reparatoris di seluruh wilayah tersebut. Ketika Honduras bahkan tidak melakukan penyelidikan terhadap penghilangan tersebut, tampak jelas bahwa peristiwa tersebut disponsori oleh negara, sehingga negara tersebut diajukan ke muka Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. Dalam sejumlah keputusan, pengadilan tersebut menyatakan bahwa Honduras telah melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika dan bahwa negara “wajib mencegah, menyelidiki dan menghukum” pelanggaran hak-hak yang dijamin dalam konvensi tersebut.16 Pengadilan juga 14 Lihat umumnya Sagi, German Reparations. Shilumim berasal dari tradisi profetik. Untuk pembicaraan tentang kedua konsep ini dan artinya dalam konteks kesepakatan reparasi, lihat Axel Frohn (ed.), Holocaust and Shilumim: The Policy of Wiedergutmachung in the Early 1950s, Washington, D.C: German Historical Institute, 1991, 1-5. 16 Velásquez-Rodrígues, Inter-Am. Ct. H.R., Ser.C,No. 4 (1988); Godinez Judgment, Inter-Am. Ct. H.R., Ser.C,No. 5 (1989); Fairen Garbi and Solis Corrales Judgment, Inter-Am. Ct. H.R., Ser.C, No. 6 (1989). Kewajiban negara untuk “mencegah, menyelidiki dan menghukum” pelanggaran dimuat dalam Velásquez Judgment pada paragraf 166. Untuk tinjauan lengkap tentang kasus-kasus ini yang ditulis oleh dua pengacara dalam proses litigasi ini, lihat Juan E. Mendez dan José Miguel Vivanco, “Disappearances and the Inter-American Court: Reflections on a Litigation Experience”, Hamline Law Review 13 (1990): 507. 15 7 memutuskan bahwa bila hak-hak tersebut dilanggar, negara wajib menjamin kompensasi bagi korban. Kasus Velásquez-Rodríguez menunjukkan bahwa kelalaian untuk mencapai keadilan melalui proses pidana bukanlah hal yang boleh dilakukan negara. Namun, kelalaian untuk melaksanakan norma-norma ini dianggap menimbulkan hilangnya hakhak perlindungan bagi korban (warga negara), sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan reparasi menurut hukum internasional. Hak-hak yang diakui dalam kasus Velásques-Rodrígues secara jelas bersifat transisional – mereka melampaui sekaligus menjembatani rezim. Meskipun hak ini pada mulanya berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan yang setara menurut hukum, begitu kewajiban ini dilanggar, timbul kewajiban “kuratif” bagi rezim penerus, seperti menyelidiki dan memberikan kompensasi. Kasus Velásquez-Rodríguez menunjukkan bahwa bila kewajiban untuk menyelidiki dan memberikan kompensasi ini tidak dipenuhi, pelanggaran ini tetap berlanjut dan rezim penerus harus memikul tanggung jawab. Sementara kewajiban pertama, yaitu untuk melindungi, bersifat prospektif dan memandang ke depan, kewajiban-kewajiban lainnya untuk menyelidiki dan memberikan kompensasi bersifat retrospektif dan melihat ke belakang; jadi mereka berkelanjutan, terbuka dan menjadi tanggung jawab rezim-rezim penerus hingga dipenuhi.17 Kewajiban-kewajiban yang diakui dalam kasus tersebut memediasi rezim pendahulu dan penerus, memperluas arti perlindungan hak asasi manusia dalam transisi. Kasus Velásquez-Rodrígues menetapkan standar kewajiban reparasi yang tinggi. Menyatakan penghilangan sebagai “pembunuhan secara melanggar hukum sebagai akibat tindakan serius yang merupakan tanggung jawab Honduras”, Pengadilan Inter-Amerika menyatakan bahwa negara wajib memberikan kompensasi “moral” dan “material” bagi mereka yang ditinggalkan berkaitan dengan kerugian akibat penghilangan tersebut.18 Lebih lanjut lagi, skema reparasi yang ekspansif dalam kasus Velásquez-Rodrígues belum memiliki preseden dalam budaya hukum Amerika Latin, yang tidak memiliki tradisi pemberian ganti rugi terhadap kerugian akibat pelanggaran oleh pihak negara.19 Kasus Velásquez-Rodrígues memberikan perspektif baru dalam memandang sifat keadilan transisional, dengan reparasi yang menyorot kedekatan antara respon pidana dan perdata. Penggunaan tindakan reparatoris dalam peradilan pidana terlihat bila dalam prinsipnya, kelalaian untuk mengadili pelanggaran berat oleh negara dianggap mempengaruhi hak-hak korban dan kewajiban-kewajiban terkait dari negara, yang kemudian ditegaskan dalam keputusan-keputusan yang menyatakan bahwa undangundang amnesti melanggar hak para korban menurut hukum hak asasi manusia regional.20 Di seluruh Amerika Latin, kasus Velásquez-Rodrígues memiliki arti bahwa bila peradilan 17 Honduras akhirnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan reparasi. Menurut Steve Hernandez dari Americas Watch (wawancara dengan pengarang, Washington, D.C., 23 Juli 1997), kompensasi sejumlah $ 300.000 diberikan dalam kasus Velásquez-Rodrígues, dan $ 250.000 dalam Godinez. 18 Velásquez-Rodrígues Judgment, Inter-Am.. Ct. H.R., Ser.C, No. 4 (1988); 46 (lihat hlm. 39 tentang kewajiban untuk memberikan kompensasi moral dan material). 19 J. Irizarry dan Puente, “The Responsibility of the State as ‘Juristic Person’ in Latin America”, Tulane Law Review 18 (1944): 408, 436 (membedakan kerugian “moral” dan “material”). Lihat juga H. Street, Governmental Liability: A Comparative Study, Cambridge: Cambridge University Press, 1953, 62-63; Linda L. Schlueter dan Kenneth R. Redden, Punitive Damages, edisi ketiga, Charlottesville, Va: Michie Butterworth, 1990 (menganalisis berbagai penerapan dalam tradisi hukum perdata). 20 Decision on Full Stop and Due Obedience Laws, Inter-Am. C.H.R, Report No. 28/92 (Argentina, 1992); Decision on the Ley de Caducidad, Inter-Am. C.H.R, Report No. 29/92, Uruguay, 2 Oktober 1992). 8 pidana gagal, respon-respon lain bisa digunakan, yaitu bahwa ada kewajiban hukum lainnya bagi para korban, berupa reparasi. Norma-norma baru yang diciptakan oleh kasus Velásquez-Rodrígues menimbulkan banyak pertanyaan. Kewajiban macam apa yang ditekankan di sini, atau apa kaitan antara kewajiban negara untuk melindungi warganya secara setara dan kewajibannya untuk “mengembalikan” hak-hak tersebut? Muncul pula pertanyaan lain: sejauh mana hak asasi manusia yang diakui dalam kasus Velásquez-Rodrígues merupakan”hak” dalam arti tradisional? Siapa yang memiliki hak tersebut? Dalam pandangan ini, siapa yang dirugikan apabila hak perlindungan setara dilanggar, apakah hanya para korban? Para kerabat yang ditinggalkan? Dan sejauh mana terdapat dampak yang lebih luas bagi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini timbul sebagai bagian dari konsekuensi lebih luas kebijakan impunitas, dengan pemberian amnesti terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh rezim lama di wilayah itu. Dengan banyaknya kebijakan amnesti di negara-negara Amerika Latin, pesan yang disuarakan oleh kasus Velásquez-Rodrígues masih selalu relevan. Setelah penderitaan akibat pemerintahan militer yang represif, penyiksaan, eksekusi dan penghilangan, pertanyaan pentingnya adalah apakah rezim pengganti dapat “melenyapkan” masa lalu mereka? Dengan melihat konteks perpolitikan masa lalu di wilayah ini, kebijakan macam ini amat aneh. Ketika Cili kembali ke pemerintahan demokratis, rentannya perimbangan kekuasaan menjadikan penghukuman bagi militer sukar dilakukan, dan rezim penerus pimpinan Aylwin menggunakan bentuk keadilan yang lain. Seperti dalam kasus Velásquez-Rodrígues, negara menjanjikan penyelidikan resmi terhadap penindasan oleh militer, dan tindakan-tindakan reparatoris.21 Skema remedial Cili ini membantu menjelaskan lebih lanjut kaitan antara pemahaman transisional tentang keadilan pidana dan reparatoris. Ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melaporkan bahwa selama berkuasanya militer terjadi ribuan penghilangan paksa dan eksekusi ekstrajudisial, Presiden Cili, dalam presentasi laporan komisi di hadapan masyarakat, menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan menyatakan bahwa reparasi merupakan “tindakan yang menggambarkan pengakuan dan tanggung jawab pemerintah untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang dibicarakan dalam laporan tersebut.”22 Dalam memikul tanggung jawab untuk memberikan reparasi, rezim penerus memikul tanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukan rezim pendahulunya. Meskipun pada awalnya terdapat tentangan terhadap pemberian ganti rugi dan tidak ada budaya hukum dengan tradisi pemberian ganti rugi untuk pelanggaran oleh pemerintah, skema remedial demikian menjadi skema yang lazim di benua tersebut. Setelah Cili, Argentina mengambil kebijakan reparasi yang bahkan lebih luas, tidak hanya memberikan kompensasi bagi mereka yang dihilangkan, namun juga bagi korban penahanan secara tidak sah selama pemerintahan junta.23 Dalam 21 Laporan penyelidikan ini berjudul Informe de la Comicíon Nacional de Verdad y Reconciliacion (Laporan Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili), kedua jilid, terjemahan Phillip E. Berryman, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993 (kemudian Laporan Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili). 22 Pidato Presiden Patricio Aylwin kepada rakyat Cili, 5 Maret 1991, ditranskrip oleh British Broadcasting Corporation, 6 Maret 1991. Undang-Undang No. 19.123 (Cili, 8 Februari 1992) memberikan kepada para ahli waris korban tunjangan seumur hidup, sejumlah uang serta tunjangan kesehatan dan pendidikan. 23 Indemnification Law, No. 24.043 (Argentina, 1991). 9 preseden terkait dalam Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Uruguay juga diperintahkan untuk memberikan reparasi.24 Preseden transisional menciptakan definisi baru tentang kewajiban negara terhadap warganya. Seperti konstitusi transisional dan sanksi pidana yang menggariskan perubahan dalam kedaulatan negara, tindakan reparatoris dapat pula melakukan hal tersebut. Reparasi transisional ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap korban, namun mereka memiliki nilai tambah di lingkup publik. Bila reparasi menjadi bagian kebijakan suksesor publik yang formal, mereka bisa secara kritis merespon kebijakan rezim pendahulu dengan memperbaiki pelanggaran terhadap perlindungan yang setara oleh hukum. Para korban penindasan oleh militer telah dituduh melakukan subversi dan dibunuh sebagai musuh negara. Mereka diculik, disiksa, dibunuh dan dihilangkan; anak-anak mereka disandera, hak milik mereka disita. Maka, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili menyarankan suatu reparasi “moral”, “untuk secara terbuka membersihkan nama baik mereka yang telah meninggal dari stigma tuduhan palsu sebagai musuh negara”.25 Sesuai dengan mandat ini, hanya beberapa hari setelah menjabat sebagai presiden, Patricio Aylwin mengadakan acara peringatan terbuka bersama rakyat Cili di stadion utama, yang pada masa pemerintahan militer dipergunakan sebagai tempat penyekapan para tahanan politik. Sementara presiden, dalam pidatonya itu, mengumumkan nama-nama mereka yang dihilangkan yang disiarkan secara langsung ke seluruh negeri, nama-nama tersebut dimuculkan pula di papan elektronik di stadion tersebut, sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf kepada para korban kesalahan pemerintahan represif sebelumnya itu. Seperti juga di masa kuno, “reparasi moral” Amerika Latin ditujukan untuk meluruskan pandangan komunitas dan mengembalikan harga diri. Reparasi moral ini bersifat kompensatoris, bukan punitif.26 Reparasi moral ditujukan untuk menghilangkan rasa malu dan rendah diri yang dialami para korban dan mengembalikan reputasi dan status mereka di mata publik. Pada pemahaman common law yang biasa tentang penghinaan, bila korban telah meninggal, tanggung jawab terhadap penghinaan ini hilang, namun tidak demikian dalam kasus penghilangan. Reparasi moral melampaui para korban dan kerabatnya saja, dan memasuki ruang publik secara keseluruhan. Pengembalian nama baik ini menunjukkan bahwa reputasi memiliki peranan yang lebih penting daripada di masa biasa; ia melayani kepentingan masyarakat dalam transisi politik. Dalam kasus penghinaan politik dan penindasan, yang terpengaruh bukan saja reputasi pribadi para korbannya. Dengan merehabilitasi mereka yang dihilangkan, negara juga secara terbuka mengakui tanggung jawabnya terhadap kesalahan tersebut. Terlebih lagi, dengan memikul tanggung jawab, rezim penerus ini menunjukkan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan negara; bahkan, pemikulan tanggung jawab oleh negara dapat mengurangi kerugian moral.27 Tindakan-tindakan perbaikan ini secara jelas ditujukan untuk memungkinkan rekonsiliasi masyarakat, untuk membawa perdamaian bagi 24 Lihat Decision on the Ley de Caducidad (dikutip dalam catatan kaki 20 di atas). Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili, 838-40. 26 Istilah “Kompensasi yang sepantasnya” dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Pasal 61 (1), ditafsirkan oleh Pengadilan Inter-Amerika sebagai kompensasi terhadap kerugian. Lihat PBB, Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violetions of Human Rights and Fundamental Freedoms (dikutip dalam catatan kaki 1 di atas), 38. 27 Lihat Kasus El Amparo (Reparations), Inter-Am. Ct. H.R. (Ser.C) ¶ 34 (14 September 1996), dicetak ulang dalam laporan Tahunan 1996. 25 10 masyarakat-masyarakat yang terpecah oleh garis politik di Amerika Latin. Praktik reparatoris transisional memiliki peran ganda: memandang ke belakang dalam memperbaiki kesalahan negara yang telah dilakukan, sekaligus memandang ke depan dalam memajukan tujuan perdamaian dan rekonsiliasi dalam transisi. Reparasi di Amerika Latin menunjukkan kompleksnya peran kebijakan reparatoris dalam masa transisi. Reparasi transisional memiliki tujuan berganda. Bila reparasi dilakukan sebagai alternatif eksplisit terhadap penghukuman, mereka menunjukkan cara-cara alternatif untuk pembersihan nama baik dan rehabilitasi seperti diajukan oleh sanksi pidana. Tindakan reparatoris transisional memikul beban tanggung jawab terhadap pelanggaran di masa lalu secara terbuka. Bahkan, pergeseran tekanan dari kerugian yang diderita para korban ke pelanggaran yang dilakukan oleh negara terlihat jelas dalam reparasi moral. Seperti dalam peradilan pidana, dengan memikul tanggung jawab secara terbuka, pelanggaran dapat diidentifikasi, dan juga pelakunya. Selain memberikan sanksi bagi para pelanggar, reparasi juga membersihkan para korban.28 Melalui respon hukum formal yang mengakui status yuridis mereka yang dihilangkan, keadilan reparatoris merekonstruksi batas-batas komunitas politik. Karena nilai guna mereka, praktik reparatoris menjadi respon yang paling penting dalam gelombang transformasi politik kontemporer. “Kebenaran dan reparasi”, suatu respon yang menggabungkan reparasi dengan penyelidikan sejarah yang dibicarakan dengan mendalam dalam bab terdahulu, telah menjadi cara utama untuk menyelesaikan konflik yang telah mengakar di seluruh Amerika Latin dan wilayah-wilayah lainnya. Perang saudara yang berkepanjangan di El Salvador dapat diselesaikan dengan janji pembentukan komisi penyelidikan dan tindakan reparatoris.29 Formula serupa mendatangkan perdamaian di Guatemala.30 Di Afrika Selatan, amnesti menjadi bagian kesepakatan perdamaian untuk ditukar dengan “kebenaran dan rekonsiliasi”. Konstitusi 1993 negara tersebut, yang bejudul “Persatuan Nasional dan Rekonsiliasi”, menyatakan: “Untuk memajukan rekonsiliasi dan rekonstruksi, amnesti akan diberikan terhadap tindakan, kelalaian dan pelanggaran berkaitan tujuan politik dan dilakukan dalam kerangka konflik di masa lalu”.31 Seperti diinterpretasikan oleh Pengadilan Konstitusional negara itu, amnesti ini diberikan dengan syarat klarifikasi terhadap kejahatan politik di masa lalu beserta reparasinya;32 maka di Afrika Selatan, kedua hal ini jelas berkaitan. Meskipun terdapat perundang-undangan tersebut, amnesti di Afrika Selatan diberikan secara bersyarat, dan dengan demikian memerlukan pertimbangan terlebih dahulu dalam bentuk penyelidikan terhadap pelanggaran di masa lalu. Janji reparasi ini menjadi insentif bagi para korban untuk bersaksi dalam proses terbuka di negeri itu; dan tindakan reparatoris dijadikan bagian dari saran-saran dalam Laporan 28 Untuk perdebatan ilmiah terkait tentang peran harga diri dalam perdebatan penghukuman/impunitas, lihat Jaime Malamud Goti, “Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?” Human Rights Quarterly 12, No. 1 (1990): 1-16. 29 Lihat PBB, El Salvador Agreements: The Path to Peace, Report of the Commission on Trith for El Salvador, DPI/1208 (1992). 30 Lihat “Guatemalan Foes Agree to Set up Rights Panel”, New York Times, 24 Juni 1994, rubrik internasional. 31 Konstitusi Afrika Selatan, bagian penutup. 32 Lihat Azanian Peoples Organization (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa and Others, 1996 (4) SA LR 671 (CC). 11 Komisi Kebenaran Afrika Selatan. Dalam semua transisi yang dibahas di atas, sanksi pidana tidak diberikan dan diganti dengan bentuk keadilan reparatoris. Penggunaan tindakan reparatoris transisional, seperti dibicarakan di atas, oleh rezim penerus sebagai ganti penghukuman menantang intuisi kita tentang apa yang membedakan sanksi pidana dan perdata. Pertentangan pidana-perdata yang umum diterima ternyata tidak berlaku dalam praktik transisional. Praktik reparatoris transisional menyikapi pelanggaran hak-hak individual, sekaligus menentukan tanggung jawab untuk tindak pidana di masa lalu, sehingga gabungan tujuan ini sukar diklasifikasikan sebagai keadilan pidana atau korektif. Praktik reparatoris transisional yang dibicarakan di atas memungkinkan pengetahuan dan pengutukan publik terhadap pelanggaran dengan cara serupa dengan sanksi pidana. Dalam common law, sifat kesalahan dianggap terikat dengan sifat kerugian, maka publik dan privat bersesuaian dengan pidana dan perdata. Seperti ditulis William Blackstone, “[P]elanggaran perdata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang dimiliki individu, yang dianggap semata-mata sebagai individu, sementara pelanggaran publik, atau kejahatan dan tindak pidana, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban publik, yang berkaitan dengan seluruh masyarakat.”33 Meskipun hal ini dalam common law merupakan perbedaan utama antara pidana dan perdata; dalam negara modern, cara berpikir kita tentang perbedaan peradilan pidana dan korektif telah mengalami perubahan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam transisi. Praktik reparatoris transisional menantang pemahaman bahwa ciri utama peradilan pidana (yang membedakannya dari peradilan perdata) adalah dominasi peran negara, karena skema reparatoris ini memiliki arti bahwa negara terlibat secara mendalam.34 Pemahaman ini juga ditantang oleh berbagai inisiatif privat dalam peradilan pidana transisional. Dalam masa transisi politik, pihak privat, seperti para korban atau perwakilannya, sering kali mendorong proses penuntutan. Inisiatif privat ini tampak jelas dalam sejarah: hampir semua usaha pengadilan penjahat Perang Dunia Kedua sejak masa pasca-perang berasal dari inisiatif privat.35 Contoh penting dalam hal ini adalah Prancis. Dalam hukum pidana kontinental, inisiatif dalam peradilan pidana sering kali dimulai oleh pihak privat, biasanya para korban, seperti dalam proses perdata.36 Keterlibatan privat para korban dalam peradilan pidana juga mulai dipertimbangkan dalam jurisprudensi sistem Inter-Amerika, di mana Komisi Inter-Amerika telah mengakui bahwa bila undang-undang amnesti disahkan, hak proses peradilan para korban terpengaruh, sehingga ada kemungkinan gangguan terhadap proses penyelidikan dan retributif. “Para kerabat atau korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki hak untuk proses hukum, untuk penyelidikan yudisial yang mendalam dan tidak memihak untuk 33 William Blackstone, “Of Public Wrongs”, dalam Commentaries on the Laws of England, jilid 4, Oxford: Clarendon Press, 1765, 1765, 5-6. 34 Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence, Boulder: Westview Press, 1990, 114-17, 145, 157-60. 35 Lihat misalnya, Fédération Nationale de Déportés et Internés Résistants et Patriotes vs. Barbie, 78 ILR 125 (Fr. cass. Crim, 1985. 36 Marry Ann Glendon, M.W. Gordon dan Christopher Osakwe, Comparative Legal Traditions: Text, Materials and Cases on the Civil and Common Law Traditions, with Special Reference to French, German, English and European Law, St. Paul: West Publishing, 1994, 95-96. 12 menentukan fakta-fakta”.37 Jaminan terhadap perlindungan setara ini berlaku bagi seluruh masyarakat dan dapat dituntut oleh para korban sebagai jaminan mendasar kedaulatan hukum. Kita keluar dari dilema dari respon rezim yang sedang melakukan liberalisasi terhadap pelanggaran negara di masa lalu. Timbullah bentuk-bentuk keadilan gabungan (hibrida) yang menggabungkan peran negara dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran publik, sekaligus memberikan ganti rugi individual. Karena, pelanggaran di masa lalu ini bukanlah semata-mata hubungan antara korban dan pelaku, namun melibatkan kebijakan negara dalam suatu komunitas. Praktik reparatoris transisional memungkinkan pengakuan terhadap pelanggaran hak individual dan kerugian yang ditimbulkannya, juga pelanggaran oleh pemerintah secara publik. Kedekatan antara peradilan pidana dan korektif ini terlihat dalam kedua bentuk respon legal dalam paradigma jurisprudensi transisional. Seperti sebelumnya dibicarakan dalam bab 2, bahkan sanksi pidana secara terbatas memajukan tujuan pengutukan kejahatan, pembersihan para korban dan sistem hukum. Terdapat kedekatan antara pemikiran-pemikiran keadilan punitif dan reparatoris dalam masa perubahan radikal. Fungsi terpenting dari hukum adalah untuk mendorong transisi pada masa-masa tersebut. Hukum menjalankan fungsi tersebut bila ia mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh negara di masa lalu, mengembalikan kehormatan para korban dan membersihkan sistem hukum.38 Reparasi dan Privatisasi setelah Komunisme Hal yang menjadi ciri utama transisi dari komunisme adalah adanya berbagai perubahan mendasar secara bersamaan: konstitusional, politik, sipil dan ekonomi. Dalam transisi berganda inilah, sebagai bagian integral untuk membangun pasar bebas, skema reparatoris di Eropa Tengah dan Timur diciptakan.39 Baik dalam pengembalian hak milik yang semula disita atau dengan kompensasi, kaitan dengan privatisasi menunjukkan peran kompleks reparasi transisional pascakomunisme: untuk memperbaiki pelanggaran negara di masa lalu, terutama penyitaan pada era Stalin, dan juga untuk memajukan kepentingan privatisasi kontemporer yang berkaitan dengan transformasi ekonomi. Kedua tujuan ini sering kali dianggap bertentangan, yang menunjukkan dilema yang spesifik bagi bekas blok Soviet dan negara-negara yang mengalami perubahan pasar serupa. Kalau begitu, ganti rugi yang bagaimana yang sesuai dengan kepentingan perubahan ekonomi, yaitu transisi ke pasar bebas? Pada akhirnya, tindakan reparatoris yang diambil berusaha mendamaikan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam penyelesaian pragmatis tujuan politik dalam transisi, reparasi pasca-komunis menantang pemahaman tradisional tentang keadilan korektif dan distributif. 37 Decision on Full Stop and Due Obedience Laws, Report No. 28/92, hlm. 32. Lihat Decision on the Ley de Caducudad (dikutip dalam catatan kaki 20 di atas), hlm. 35, 39. 38 Tujuan demikian dielaborasi dalam teori penghukuman Kantian. Lihat Immanuel Kant, The Metaphysical Elements of Justice: Part 1 of the Metaphisics of Morals, terjemahan J.I. Ladd, Indianapolis: Bobb-Merrill, 1965. 39 Untuk analisis ilmiah tentang berbagai skema, lihat umumnya “A Forum on Restitution”, East European Constitutional Review 2 (1993): 30. 13 Pada awal tahun 1991, kurang dari dua tahun sejak revolusi 1989, perdebatan di Republik Ceko tentang apa yang harus dilakukan dengan kejahatan-kejahatan politik masa komunis berakhir dengan Undang-Undang Rehabilitasi Ekstrayudisial.40 Ditujukan untuk memberikan restitusi bagi para korban penindasan politik era komunis, undangundang ini menyatakan bahwa properti apa pun yang didapatkan secara paksa haruslah dikembalikan. Dalam perdebatan parlementer tentang undang-undang ini, tampak jelas tujuan berganda restitusi ini: banyak dari pendorong undang-undang ini mendukungnya atas dasar ekonomi. Karena di bekas Cekoslowakia negara praktis memonopoli alat-alat produksi, pengembalian properti yang disita dijustifikasi sebagai “restitusi natural”, sebagai cara yang efisien untuk melakukan privatisasi, karena ia dapat memfasilitasi pemindahan properti negara ke kepemilikan swasta. Sebaliknya, para penentang undangundang ini menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang secara mendasar memandang ke belakang, yang mengurangi kemungkinan kaitan kepemilikan yang lebih bebas. Kedua pihak ini benar: konstruksi hak milik yang pertama memajukan sasaran masa kini untuk menciptakan pasar swasta, dan undang-undang ini mengkonstruksi pemahaman hak milik swasta. Setelah diambilnya langkah-langkah pertama dalam transisi politik negara dapat memulai proyek restitusinya yang berskala besar ini. Bahwa reparasi dalam transisi pasca-komunis memiliki kepentingan politis dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Kompensasi Hungaria. Pendahuluan undang-undang ini menyatakan bahwa ia memiliki tujuan “ganda” untuk “menciptakan keamanan berusaha dalam kondisi ekonomi pasar dan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh negara”. Justifikasi “hak milik baru” ini didasarkan pada perlindungan klaim hak milik di masa lalu: Negara yang mengakui dan melindungi hak milik pribadi memiliki kewajiban moral untuk mengambil tindakan dan memberikan ganti rugi finansial bagi mereka yang hak miliknya dirugikan. Untuk kepentingan mengembangkan kaitan kepemilikan yang lebih sehat dalam ekonomi pasar modern, negara berkehendak untuk mengembalikan kerugian hak milik pribadi yang dialami ... dengan memberikan ganti rugi parsial kepada bekas pemilik.41 Seperti dijelaskan dalam pendahuluan undang-undang ini, anggapan tentang keberadaan hak milik “di masa lalu” ini merupakan fiksi yudisial untuk menjustifikasi dan memajukan konstruksi hak milik secara sesegera mungkin. Dan, sementara pengakuan terhadap hak milik demikian bersifat ex post, kostruksi ini dilakukan untuk kepentingan ekonomi yang memandang ke depan. Ketika Pengadilan Konstitusional negara ini menegaskan kostitusionalitas skema kompensasi ini, skema tersebut dikatakan sebagai “novation”, yang berarti bahwa “hak-hak” (dan pelanggarannya di masa lalu) digunakan untuk menjustifikasi hak milik di masa kini. Konflik antara kepentingan restitusi dan privatisasi, jika ada, dapat diselesaikan dengan tidak menetapkannya secara absolut “semua” atau “tidak sama sekali”, yaitu dilema tentang restitusi sepenuhnya terhadap properti yang disita. Keputusannya adalah berkompromi dengan apa yang disebut “ganti rugi parsial”. Mengaitkan sasaran reparatoris dengan kepentingan ekonomi dilakukan oleh masing-masing negara di wilayah ini. Bahkan, perimbangan kepentingan selalu berubah 40 Law on Extrajudicial Rehabilitation (“Large Restitution Law”) (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1991), dicetak ulang dalam Central and Eastern European Legal Texts (Maret 1991). 41 Compensation Laws, No. 25 (Hungaria, 1991). 14 dalam transisi. Maka, dalam Traktat Unifikasi, kedua Jerman menyepakati restitusi luas: menurut prinsip “restitusi mendahului kompensasi” dalam traktat itu, bila ada properti yang disita, selain pada masa pendudukan Soviet, ia akan dikembalikan kepada mantan pemilik atau ahli warisnya.42Setelah proyek ini dimulai, prinsip restitusi luas ini mendapatkan tentangan karena menghambat privatisasi, sehingga klaim restitusi diubah menjadi kompensasi. Ketika skema kompensasi ini ditentang berdasarkan perlindungan konstitusi Jerman terhadap penyitaan hak milik, konstitusionalitas skema ini tetap dianggap berlaku. Menurut pengadilan, larangan terhadap penyitaan dalam konstitusi, sebagai respon terhadap penyitaan pada masa komunis, tidak mensyaratkan pengembalian properti tersebut kepada pemilik semula, atau memberikan kompensasi apa pun.43 Mirip dengan itu, ketika undang-undang kompensasi parsial di Hungaria ditentang, Pengadilan Konstitusional menegaskan keabsahannya, yang menyatakan bahwa restitusi bukanlah “hak”, sehingga parlemen harus menunjukkan bahwa perlakuan khusus tersebut benar-benar merupakan kepentingan publik.44 Dengan cara ini, rezim yang menggantikan pemerintahan komunis satu partai dapat menggabungkan berbagai tujuan dan program restitusi mereka. Prinsip yang memandu hal ini adalah harmoni, sehingga reparasi untuk pelanggaran di masa lalu dijustifikasi atas dasar yuridis, sebagai hak menurut hukum yang sesuai dengan tujuan transisi ekonomi.45 Masalah privatisasi melalui reprivatisasi yang muncul di Jerman dan Republik Ceko mungkin bisa membuat negara-negara lain enggan melakukan restitusi berskala besar.46 Maka, meskipun Polandia memperdebatkan restitusi terhadap klaim atas properti milik mereka yang hartanya disita pada masa komunis, begitu masa komunisme berakhir, tidak pernah tercipta konsensus tentang kebijakan restitusi. Rancangan Undang-Undang Reprivatisasi negara itu, bila berlaku, akan menyelesaikan konflik antara keadilan reparatoris dan kebijakan privatisasi, dengan memberikan kompensasi secukupnya 42 Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman, “Agreement with Respect to the Unification of Germany”, 31 Agustus 1990, BGBI.II, diterjemahkan dan dicetak ulang dalam International Legal Materials 30 (1991): 457 (kemudian “Traktat Unifikasi Jerman”). Prinsip “restitusi mendahului kompensasi” ini ditemukan dalam Pasal 41 traktat ini. Detail-detail skema ini ditemukan dalam lampiran II traktat ini, sebagai bagian Kesepakatan Bersama 15 juni 1990, sebelum dimuat dalam traktat. 43 Land Reform Decision, Combined Nos. I BvR 1170/90, 1175/90, Neue Juristiche Wochenschrift 1959 (Pengadilan Konstitusional Jerman, 1991). Lihat juga Keith Highet, George Kahale III dan Charles E. Stewart, “Former German Democratic Republik – Soviet Occupation Expropriations – Constitutionality of German Unification Agreement Clause Providing that Cash Compensation is Sole Remedy ‘Land Reform’ Decision”, American Journal of International Law 85 (1991): 690. 44 Judgment of July 3, 1991, No. 28/1991 (IV.3) AB, Magyar Kozlony No. 59/1991 (Hungaria, Alkotmánybíriság [Pengadilan Konstitusional] (terjemahan tidak resmi dalam arsip Michigan Journal of International Law). Keputusan ini juga dirujuk dalam literatur sebagai “kasus kompensasi III”, Untuk analisis undang-undang kompensasi dan ketiga keputusan Pengadilan Konstitusional yang memodifikasinya, lihat Ethan Klingsberg, “Safeguarding the Transition”, East European Costitutional Review 2, No. 2 (musim semi 1993): 44. 45 Untuk diskusi tentang beberapa pertimbangan moral tentang restitusi di wilayah ini, lihat Claus Offe, Varieties of Transition – The East European and East Germany Experience, Cambridge: MIT Press, 1996. 46 Lihat Vojtech Cepl, “A Note on the Restitution of Property in Post-Communist Czechoslovakia”, Journal of Communist Studies 7, No. 3 (1991): 368-75. 15 terhadap korban penyitaan, dari pendapatan perusahaan negara yang diprivatisasi.47 Hal ini merupakan titik tengah antara tujuan reparatoris dan distributif. Reparasi pasca-komunis menggambarkan paradigma konsep tradisional tentang keadilan reparatoris. Ia bukanlah dasar yang ideal, namun mencerminkan berbagai sasaran yang mewarnai masa pergolakan politik yang luar biasa. Praktik pada masa transisi adalah berupa pemberian pembayaran yang dijustifikasi atas dasar untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan sekaligus memajukan sasaran ekonomi transisional. Bersamaan dengan usaha negara untuk memperbaiki kesalahan rezim lama yang melakukan perampasan, hak-hak di masa lalu digunakan untuk menjustifikasi redistribusi hak milik di masa kini. Dengan cara ini, prinsip reparatoris dipakai untuk melakukan transisi menuju ekonomi pasar. Kewajiban reparatoris ditanggung, dan klaim hak diberikan, bila mereka bersesuaian dengan kepentingan politis lain dari transisi. “Hak-hak” properti ex post facto dibentuk dan dijustifikasi selama mereka bersesuaian dengan transformasi ekonomi. Dalam konsepsi yang kompleks ini, skema reparatoris transisional memajukan secara bersamaan berbagai bentuk perubahan yang berbeda-beda. Bila tindakan reparatoris transisional ditujukan untuk memajukan tatanan baru ekonomi, skema-skema ini menciptakan satu kelas baru pemilik properti dengan konsekuensinya terhadap transformasi politik. Jelas, modal yang terkumpul memberikan andil besar dalam komunitas politik. Terlebih lagi, bila skema reparatoris menjadi syarat untuk dukungan terhadap pemerintah atas dasar politik, mereka bisa mempengaruhi rekonstruksi keanggotaan ekonomi dan politik. Kelompok kepentingan restitusi telah mempengaruhi perkembangan partai politik di Republik Ceko, Hungaria dan Bulgaria.48 Bila kebijakan restitusi disyaratkan atas penindasan politik di masa lalu, kebijakan tersebut menunjukkan kedekatan dengan respon transisional lainnya, seperti tindakan administratif yang secara terbuka merekonstruksi batas-batas komunitas politik. Dilema Keadilan Reparatoris Transisional dan Kedaulatan Hukum Prinsip kedaulatan hukum manakah yang memandu keadilan reparatoris dalam masa transisi? Proyek reparatoris dalam berbagai masyarakat dalam konteks gejolak politik yang luar biasa memajukan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan perubahan politik radikal, di luar tujuan-tujuan remedial yang lazim, seperti rekonsiliasi masyarakat dan transformasi ekonomi. Keadilan reparatoris transisional memajukan sasaran politik yang berada di luar prinsip keadilan korektif konvensional. Dalam skema-skema reparatoris yang kompleks ini, prinsip apa yang menjustifikasi keadilan reparatoris transisional? Pertanyaan tentang apa yang menjadi panduan ini timbul dalam perdebatan tentang restitusi pasca-komunisme. Tantangan menghadapi reparasi di wilayah ini, menurut Presiden Republik Ceko dan mantan oposan, Václav Havel, adalah “jika semua 47 Alberto M. Aronovitz dan Miroslaw Wyrzykowski, “The Polish Draft Law on Reprivatization: Some Reflections on Domestic and International Law”, Swiss Review of International and European Law (1991): 223. 48 Untuk analisis perseptif tentang bagaimana kelompok kepentingan restitusi mempengaruhi perkembangan partai transisional, lihat Jonathan Stein, “The Radical Czechs: Justice as Politics” (Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Keadilan dan Transisi di Venesi, oleh Foundation for a Civil Society, November 1993). 16 orang menderita, mengapa hanya beberapa yang mendapat kompensasi?”49 Pada umumnya, norma panduan yang utama adalah kerugian yang telah dialami. Kerugian pada masa pemerintahan sebelumnya dipahami (sesuai dengan konteks wilayah tersebut) secara universalis dan egaliter. Premis-premis ini ditarik dari nilai utama kedaulatan hukum dalam masa komunisme. Jon Elster, memandang bahwa “isu utama ... adalah ... perlakuan yang setara ... Amanat penting untuk mengingat bahwa pada dasarnya semua menderita dalam masa komunisme .... Kompensasi sepenuhnya bagi beberapa korban saja tidak bisa dibela sebagai suatu bentuk konkret dari ide tentang kompensasi universal”.50 Berawal dari klaim bahwa dalam masa totaliter sebelumnya semua orang mengalami penderitaan, mereka yang menentang tidakan reparatoris pasca-komunisme beralasan bahwa satu-satunya skema reparatoris yang adil adalah yang bersifat universal. Karena jelas bahwa skema tersebut tidaklah mungkin disebabkan kurangnya sumber daya yang tersedia, argumen universalitas ini malah menjadi dasar untuk menolak segala bentuk pemberian kompensasi, yang sebenarnya paradoksal. Bagaimanapun, keadilan reparatoris di bekas blok komunis amat dilemahkan karena tiadanya kompensasi secara menyeluruh. Asumsi egaliter utama bahwa “semua orang menderita” dalam masa rezim lama memliki dua klaim tentang reparasi berdasarkan pada kerugian yang dialami, klaim universalitas dan kesetaraan. Bila reparasi universal ditempatkan sebagai idea, skema reparatoris transisional menjadi terkutub: semua atau tidak sama sekali. Argumen egaliter yang digunakan untuk menentang reparasi transisional menggemakan eksperimen sosialis – yang telah gagal. Namun, dalam sistem demokrasi yang mapan, melakukan tindakan perbaikan, yang bahkan hanyalah sebagian, diterima sebagai bagian dari tindakan korektif.51 Kedaulatan hukum yang berlaku umum untuk kebijakan pemerintah ini adalah bahwa mereka dijalankan langkah demi langkah.52 Nilai-nilai perlindungan yang setara menunjukkan bahwa kasus serupa; suatu kebijakan korektif yang adil harus mempertimbangkan klaim-klaim individual dan keseruapaan antaranya. Tantangan terhadap skema reparatoris pasca-komunis ini juga terlihat dalam masalah distribusi. Dari perspektif ini, kebijakan distributif yang adil harus memperhatikan klaim-klaim dari anggota lain dalam masyarakat. Meskipun universalitas bukanlah panduan utama terhadap keadilan korekatif secara konvensional, ia perlu diperhatikan pada masa setelah komunisme. Dengan menjadikan kerugian sebagai dasar keadilan reparatoris pada masa transisional, skema-skema ini menjadi rentan karena memiliki dampak yang terbuka, berpotensi untuk memasukkan segala bentuk ketidakadilan di masa lalu. Dengan potensi klaim yang tidak terbatas ini, batasan yang mungkin ditentukan oleh ketersediaan sumber daya. Namun, masalah ini bisa agak berkurang karena sejarah politik ekonomi terpimpin di wilayah tersebut, karena properti yang dipermasalahkan berada di tangan negara: 49 Václav Havel, Open Letters: Selected Writings, 1965-1990, ed. Paul Wilson, New York: Random House, Vintage Books, 1992. 50 Jon Elster, “On Doing What One Can: An Agreement against post-Communist Restitution and Retribution”, East European Constitutional Review 1, No. 2 (musim panas 1992): 16 (tekanan ditambahkan). 51 Untuk suatu rangkuman yang bagus, lihat John Chapman (ed.), Compensatory Justice: Nomos XXXIII, New York: New York University Press, 1991. 52 Lihat Peter Schuck, “Mass Torts: An Institutional Evolutionist Perpective”, Cornell Law Review 80 (1995): 941. 17 negara terimplikasi sebagai pemilik properti atau sebagai pelaksana skema restitusi yang memerlukan kerja sama dari pihak ketiga. Kedekatan antara skema korektif dan distributif dalam kondisi transisional ini cukup menjelaskan dorongan untuk menggunakan universalitas sebagai nilai kedaulatan hukum yang memandu transisi. Kritik terhadap reparasi transisional dari teori ideal menentang skema-skema ini karena tidak bersifat universal, dengan “kerugian” sebagai dasar pemberian reparasi. Namun, sementara kerugian bisa dijadikan justifikasi reparasi transisional, prinsip-prinsip lain yang memberikan batas-batas juga digunakan, yang mengalihkan fokus dari kerugian ke hak. Reparasi dalam sistem liberal dijustifikasi dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak individual. Di negara-negara liberal, inilah dasar untuk keadilan korektif.53 Fokus terhadap hak-hak individual sebagai ciri utama sistem hukum liberal ini terlihat dalam dominasi keadilan korektif dalam sistem demokrasi yang sudah mapan. Maka, skema-skema transisional, terutama setelah komunisme, ketika terjadi bersamaan dengan transformasi politik dan ekonomi, melampaui pemahaman konvensional tentang keadilan korektif dan distributif. Pemberian hak milik atas properti sebagai akibat pelanggaran di masa lalu dikonstruksikan secara ex post dan secara bersamaan merujuk pada diri sendiri dan menjustifikasi distribusi properti di masa kini. Pengakuan terhadap pelanggaran di masa lalu meletakkan dasar untuk konstruksi kontemporer hak-hak properti yang baru. Skema reparatoris memediasi tujuan-tujuan transisi yang memandang ke belakang dan ke depan. Reparasi Politik: Prioritas Transisional untuk Kesetaraan Politik Di berbagai budaya hukum, praktik reparatoris sering kali dilakukan pada masa-masa pergolakan politik. Reparasi disepakati sebagai respon legal yang paling populer pada masa transisi, bahkan di negara-negara yang umumnya tidak menyukai remedi seperti itu. Kompensasi adalah hal kontroversial di negara-negara yang tradisi hukumnya bukanlah common law; sementara, dalam budaya hukum kontinental, pelanggaran berat terhadap hak umumnya dianggap tidak bisa diperbaiki dengan pemberian ganti rugi moneter.54 Serupa dengan itu, karena alasan kebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi terpimpin, yang dibicarakan di bagian awal dalam bab ini, terdapat pula penolakan terhadap reparasi setelah berakhirnya komunisme. Legalitas sosialis menempatkan nilai kecil atau tidak sama sekali terhadap pengakuan hak-hak milik individual.55 Akibatnya, usaha untuk memperbaiki perlakuan politik di masa rezim lama dengan memberikan kompensasi atau restitusi atas dasar politik merupakan suatu hal yang menandakan perubahan sikap dibandingkan masa lalu. Pertanyaan utama tentang keadilan adalah: dari semua pelanggaran yang dilakukan pada masa penindasan yang sudah berlaku, ketidaksetaraan manakah yang memerlukan perbaikan? Perlakuan berbeda manakah yang menjustifikasi reparasi 53 Untuk perspektif liberal, lihat Randy E. Barnett, “Compensation and Rights in the Liberal Conception of Justice”, dalam Nomis XXXIII: Compensatory Justice, ed. John Chapman, New York: New York University Press, 1991, 311-29. 54 Lihat Schlueter dan Redden, Punitive Damages. Lihat juga B.S. Markesinis, A Comparative Introduction to the Law of German Torts, New York: Oxford University Press, 1990. 55 Allen Buchanan, Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism, New York: Rowman and Littlefield, 1984, 40-85. 18 suksesor? Kerugian saja, seperti dibicarakan di atas, tidak menjadi satu-satunya dasar reparasi pada masa transisi. Karena setelah pemerintahan represif yang sistematis, kerugian tidaklah terbatas dan bukan menjadi prinsip yang restriktif. Preseden reparatoris tentang perlakuan yang berbeda pada masa pemerintahan represif di masa lalu menunjukkan bahwa prinsip relevan tentang perbedaan perlakuan yang layak mendapat kompensasi menentukan kerugian mana yang mendapat perbaikan, adalah prinsip penindasan politik. Praktik transisional di atas menunjukkan bahwa perlakuan negara di masa lalu yang layak mendapatkan kompensasi terutama berkaitan dengan diskriminasi di masa lalu atas dasar politik; prinsip utama kerugian yang dapat dikompensasi pada masa transisi berusaha untuk memperbaiki kesalahan penindasan politik di masa lalu. Kompensasi sering kali dijustifikasi atas dasar hak yang diciptakan dalam hukum natural atau internasional, sebagai sumber norma-norma yang berkelanjutan yang mengabaikan perubahan politik.56 Dalam hukum internasional, dukungan terkuat adalah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang paling berat, yaitu norma-norma “jus cogens”.57 Reparasi yang dijustifikasi atas dasar prinsip penindasan politik memediasi tujuan transisi yang memandang ke belakang dan depan. Kebijakan reparatoris yang berdasar pada prinsip perlindungan terhadap penindasan politik dijustifikasi atas dasar mandat negara untuk memberikan perlindungan secara setara. Semua pemerintah wajib melindungi semua warga-negaranya secara setara di muka hukum; pelanggaran kewajiban ini adalah dasar untuk melakukan revolusi.58 Kesetaraan di muka hukum sering kali menjadi nilai yang mendasari revolusi, namun setelahnya, ke mana perginya hak untuk mendapat perlindungan yang setara ini? Bila perbaikan dilakukan dengan memandang penindasan politik di masa lalu, ia menghidupkan kembali dasar revolusi dan memajukan rekonstruksi hak-hak warga negara. Perhatian terhadap hak-hak kesetaraan ini memiliki signifikansi yang melampaui individu-individu yang terpengaruh dan menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Bila rezim penerus memberikan reparasi terhadap korban penindasan politik rezim lampau, tindakan demikian menegaskan bahwa hak-hak warga negara akan dilindungi secara setara. Pengakuan hak-hak individual menggariskan suatu garis baru yang memberikan keamanan individu dari negara, yang merupakan tanda perubahan menuju liberalisasi. Tindakan reparatoris transisional menarik garis yang memisahkan masa lalu dengan masa kini, dari penindasan politik, dan dengan demikian, menjalankan tindakan dan ritual yang dikaitkan dengan sistem hukum negara liberal. Dilema Titik Awal Usaha reparatoris suksesor biasanya diambil dengan prinsip penindasan politik, terhadap hak-hak yang diakui secara retroaktif oleh rezim transisional. Dalam proses konstruktif ini, pertanyaan penting yang muncul tentang kebijakan reparatoris adalah dari mana menarik titik awal? 56 Lihat misalnya, Law on Extrajudicial Rehabilitation (menggunakan hukum internasional sebagai dasar hak atas properti) (dikutip dalam catatan kaki 40 di atas). 57 Lihat catatan kaki 40 di atas. 58 Lihat Steven J. Heyman, “The First Duty of Government: Protection, Liberty, and the Fourteenth Amendment”, Duke Law Journal 41 (1991): 507. 19 Bagaimana cara masyarakat transisional menyelesaikan dilema titik awal? Dalam negara-negara demokrasi mapan, pemerintahan suksesor biasanya melanjutkan kewajiban pemerintah sebelumnya;59 terdapat asumsi kontinuitas negara dan pemerintah penerus dianggap bertanggung-jawab untuk tindakan pendahulunya. Namun, bila rezim penerus menggantikan serangkaian pemerintahan yang represif, apa kewajiban pemerintah penerus ini, yang hendak memajukan kedaulatan hukum? Apakah intuisi tentang kontinuitas legal dalam pergantian pemerintahan berarti bahwa semua kewajiban tersebut harus ditanggung? Sejauh mana rezim penerus mewarisi kewajiban yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran hak oleh rezim yang lama? Keadilan reparatoris berkaitan dengan pelanggaran di masa lalu, namun pengakuan hak oleh rezim pengganti menimbulkan pertanyaan: apa yang memandu kegiatan reparatoris tersebut? Preseden transisional menunjukkan bahwa hanya kewajiban-kewajiban tertentu saja yang diwariskan oleh pelanggaran rezim lama. Negara-negara berbeda dalam tingkat komitmennya terhadap liabilitas atau pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan pelanggaran di masa lalu. Garis dasar apa yang tepat dalam perhitungan penggantian kerugian? Masalah ini terlihat dalam transisi kontemporer setelah pendudukan berulang-ulang dan gelombang penindasan politik. Di bekas blok komunis, pertanyaan tentang titik awal ini menimbulkan perdebatan sengit. Sejarah invasi berulang-ulang, pendudukan Nazi masa Perang Dunia Kedua yang dilanjutkan pendudukan Soviet, berarti bahwa setelah keruntuhan blok Soviet, perdebatan tentang titik awal tentang penindasan politik dan korban-korban manakah yang akan mendapatkan kompensai menjadi inti perdebatan publik di seluruh wilayah ini. Meskipun sejarah masa lalu wilayah ini sering kali digambarkan sebagai masa-masa penindasan yang berkelanjutan, pertimbangan terhadap tindakan reparatoris menimbulkan perdebatan publik pertama tentang konsekuensi penindasan berkelanjutan ini terhadap titik awal transisi ke arah liberal. Pertanyaan dan pilihan yang ada memiliki muatan politis, karena terkait dengan pendudukan Nazi dan Soviet, dan dengan penarikan garis pengembalian ke kedaulatan domestik. Perdebatan titik awal ini menggambarkan persaingan politik tentang signifikansi sosial pengakuan terhadap hak-hak reparatoris transisional. Bila garis tanggung jawab suksesor ditarik secara bersesuaian dengan pengembalian ke kedaulatan internal, titik awal ini mungkin bisa dijustifikasi dari perspektif legal, yaitu kembali ke kedaulatan hukum. Namun, pilihannya tetaplah kontroversial secara politis. Pilihan titik awal restitusi harus memilih korban-korban berbagai spektrum penindasan dan kelompok kepentingan politisnya. Dilema ini sedemikian parahnya sehingga di beberapa negara, seperti Polandia, ia menghalangi tercapainya kesepakatan tentang kebijakan restitusi yang akan diambil. Perdebatan yang berkepanjangan dan panas tentang titik awal di Eropa Timur menunjukkan bahwa kebijakan reparatoris pada masa-masa demikian tidak bisa menolak pengaruh politisasi, terutama bila skema kompensatoris digunakan untuk melakukan hal-hal lainnya seperti reformasi ekonomi dan privatisasi. Di banyak negara di wilayah itu, tahun 1948 ditentukan sebagai titik awal, yang dijustifikasi sebagai akhir pendudukan asing dan kembalinya kedaulatan domestik. Di Jerman, misalnya, penyitaan sebelum tahun 1949 pada awalnya tidak dijadikan bagian 59 Lihat Lassa Oppenheim, “Peace”, Vol. 1, pengantar dan pt. 1 Oppenheim’s International Law, ed. Robert Jennings dan Arthur Watts, London: Longman Group, 1992, 234-35. 20 dari program restitusi negara ini;60 dan baru setelah timbul tekanan dari pihak luar (Amerika), pogram restitusi ini diperluas untuk mencakup perampasan pada era Nazi. Sementara perampasan yang dilakukan setelah terbentuknya Republik Demokratik Jerman akan direstitusikan kepada mantan pemiliknya, properti yang disita pada masa pendudukan Soviet di Jerman Timur antara tahun 1945 dan 1949 hanya dikompensasi sebagian. Undang-Undang Rehabilitasi Ekstrayudisial Cekoslowakia juga menjadikan tahun 1948 sebagai garis batas, yang dijustifikasi sebagai saat pengambilalihan kekuasaan oleh komunis dan dimulainya pemerintahan satu partai.61 Meskipun undangundang restitusi Cekoslowakia ini mengakui “berbagai ketidakadilan dari masa sebelumnya”, seperti perampasan yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, ia tidak mengembalikan properti milik orang Yahudi yang dirampas oleh Nazi atau mengembalikan properti dua juta warga Sudeten (etnik Jerman) yang dirampas pada waktu mereka diusir setelah perang berakhir. Potensi diskriminatoris dari penarikan titik awal ini menjadi perdebatan tingkat konstitusional di wilayah ini. Isu ini menimbulkan konflik antara para politisi dengan para pejabat hukum. Di Hungaria, masalah titik awal ini menjadi titik fokus pertikaian sengit dan berkepanjangan antara Parlemen dan Pengadilan Konstitusional. UndangUndang Kompensasi Hungaria hanya akan memberikan restitusi bagi mereka yang propertinya dinasionalisasikan secara paksa setelah tahun 1949. Dalam sejumlah keputusan kontroversial, Pengadilan Konstitusional menyatakan bahwa undang-undang tersebut “tidak memiliki dasar konstitusional” untuk menggunakan tahun 1949 sebagai titik awalnya, karena mengabaikan properti yang disita sebelum tahun 1949, seperti milik warga Yahudi pada masa perang dan milik warga Jerman setelah perang berakhir. Prinsip kesetaraan, menurut Pengadilan Konstitusional, mengharuskan garis batas ini ditarik mundur ke tahun 1939 dan memperlakukan korban-korban perampasan pada era Nazi setara dengan korban-korban perampasan era Stalin.62 Dalam keputusan serupa, Pengadilan Konstitusional Ceko, dalam meninjau Undang-Undang Rehabilitasi Ekstrayudisial, menyatakan bahwa titik awal harus dimundurkan untuk memungkinkan restitusi bagi korban-korban penyitaan era Nazi.63 Setelah empat puluh tahun pemerintahan Komunis dan penentangannya secara ideologis terhadap hak atas properti, pertanyaan tentang bagaimana mengakui hak atas properti dalam hukum memiliki muatan politis. Dengan demikian, jurisprudensi konstitusional tentang kontroversi titik awal ini berusaha untuk mendepolitisasi isu ini dan memindahkannya dari meja pertimbangan politik transisional. Dalam pengadilan konstitusional, kontroversi titik awal tentang restitusi pasca-komunis ini diperlakukan sebagai masalah konstitusional, dengan isu-isu terpentingnya yaitu ketaatan pada prinsip perlindungan yang setara dan kedaulatan hukum. Namun, meskipun tidak ada perlindungan terhadap hak atas properti dalam hukum yang telah ada, parlemen dan pengadilan suksesor di wilayah ini menggunakan hukum yang lebih tinggi, seperti hukum internasional, untuk mengkonstruksi hak. Misalnya, dalam tinjauan yudisial terhadap skema kompensasi Hungaria, justifikasi konstitusional diberikan berdasarkan “hak”; 60 Lihat umumnya “Traktat Unifikasi Jerman.” Law on Extrajudicial Rehabilitation (dikutip dalam catatan kaki 40 di atas), pasal 1, pargraf 1. 62 Lihat umumnya Land Reform Decision. Lihat juga Offe, Varieties of Transition. 63 Decision of the czech Constitutional Court, 12 Juli 1994. 61 21 klaim kompensasi dianggap timbul dari “novasi/pembaruan premis-premis lama”.64 Serupa dengan itu, Undang-Undang Rehabilitasi Ekstrayudisial Ceko mendasarkan perlindungan terhadap hak atas properti pada hukum internasional yang melindungi individu dari perampasan tanpa kompensasi.65 Dalam konteks transisi politik, dilema titik awal ini merupakan teka-teki yang membingungkan. Menarik garis pertanggungjawaban legal negara untuk pelanggarannya di masa lalu mengkonstruksi suatu pemahaman sosial tentang kontinuitas legal dan ketaatan pada kedaulatan hukum. Sebaliknya, menarik titik awal juga mengkonstruksikan diskontinuitas legal dari rezim lama, dan merupakan suatu bentuk “mengembalikan” ke keadaan semula kesalahan-kesalahan di masa lalu. Contohnya adalah Hungaria dan Ceko, di mana titik awal yang relevan ditarik dan dijustifikasi berdasarkan awal berkuasanya rezim yang “melanggar hukum”. Dengan pandangan ini, titik awal memiliki suatu diskontinuitas juridis dengan rezim komunis, sementara di pihak lain menegaskan kontinuitas. Kontroversi titik awal reparasi ini memunculkan isu terpenting dalam transisi tentang konstruksi kontinuitas negara berkaitan dengan tanggung jawab reparatoris dan identitas politik. Contohnya, dalam Traktat Unifikasi Jerman, titik awal tahun 1949 dijustifikasi sebagai akhir masa pendudukan Soviet. Namun penetapan titik awal ini tidak bisa dirasionalisasi atas dasar keabsahan rezim sebelumnya, karena masa pendudukan Soviet ini sekurang-kurangnya sama represifnya dengan rezim satu partai domestik. Namun, prinsip yang memandu penentuan titik awal ini dijustifikasi dengan memasukkan dikotomi kedaulatan internal vs. eksternal, dan prinsip pemandunya sejauh mana terdapat kontinuitas kedaulatan, yaitu kontinuitas legal dan premis-premis suksesi rezim. Ketersediaan suatu negara untuk memikul tanggung jawab rezim yang mendahuluinya adalah simbol kontinuitas dalam identitas negara, seperti di Amerika Serikat pascaPerang Saudara dalam menyikapi hutang-hutang Perang Konfederasi, suatu tindakan diskontinuitas dari rezim ini.66 Remedi atau upaya legal reparatoris transisional merupakan tindakan yang menggariskan kontinuitas kewajiban, dan dengan demikian membangun identitas politik. Dalam berbagai transformasi politik, seperti digambarkan kasus-kasus pascarezim militer dan pasca-komunis, reparasi merupakan respon sosial yang dapat diterima terhadap penindasan dan juga merupakan cara mendorong transformasi politik dan ekonomi. Reparasi merupakan cara untuk menarik garis batas masa lalu. Ini adalah peran reparasi transisional yang paling simbolis, memajukan tujuan transformasi politik. Usaha reparatoris dikaitkan dengan rekonstruksi identitas politik. Skema reparatoris mengembalikan kepada para korban status juridis dan politis yang semula terampas. Misalnya, dalam reparasi Amerika Latin, di mana perampasan status politis dan juridis dilakukan dengan cara-cara di luar hukum, bentuk rehabilitasi politik yang diambil adalah permintaan maaf secara publik, yaitu pencabutan kembali stigma politis secara terbuka 64 Judgment of july 3, 1991 (dikutip dalam catatan kaki 44 di atas), paragraf 3.3-4. Law on Extrajudicial Rehabilitation, bagian 1, paragraf 1. 66 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 4: “Baik Amerika Serikat maupun negara lain tidak akan menanggung atau membayarkan hutang atau kewajiban yang timbul akibat membantu insureksi atau pemberontakan terhadap Amerika Serikat ... semua hutang, kewajiban dan klaim demikian akan dianggap ilegal dan tidak berlaku”. 65 22 dan resmi.67 Misalnya, dalam pidato Presiden Aylwin kepada rakyat Cili, di mana ia meminta maaf atas nama pemerintah dalam suatu arena publik. Dengan merehabilitasi mereka yang dihilangkan, reparasi menarik garis dari pelanggaran di masa lalu, dan membentuk suatu identitas politik baru. Keadilan reparatoris adalah bentuk rehabilitasi politik yang juga lazim di skema-skema pasca-komunis. Setelah perubahan politik di wilayah ini, banyak udang-undang yang disahkan untuk merehabilitasi korban-korban penindasan era Stalin.68 Selain rehabilitasi melalui perundang-undangan, terdapat pula tinjauan kasus demi kasus terhadap hampir sejuta kasus pidana mereka yang semula dicabut kewarganegaraannya dan diusir dari negaranya.69 Rehabilitasi korban-korban pembalasan dendam politik mencakup pembayaran kompensasi, dan bila relevan, pengembalian status kewarganegaraan. Pengembalian status politik dilakukan dengan pemberian lambang-lambang, seperti gelar atau medali – bahkan properti digunakan untuk hal ini – sebagai konstruksi publik kasus politik, identitas dan keanggotaan dalam komunitas.70 Kelompok-kelompok yang semula ditindas direhabilitasi melalui keputusan presiden.71 Secara luas, sejarah suatu negara direhabilitasi dengan penamaan ulang jalan-jalan dan monumennya. Undang-undang Rehabilitasi politik secara eksplisit mengakui dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan akibat penindasan politik dengan berbagai cara dari reparasi konvensional hingga ingatan kolektif.72 Di sini tampak peran konstruktif dari penggantian kerugian dalam mendefinisikan sejarah negara yang penting dalam identitas politiknya. Penundaan Keadilan Reparatoris: Dilema Perjalanan Waktu Bagian terakhir ini akan mengeksplorasi keadilan reparatoris setelah suatu jangka waktu tertentu. Apa yang terjadi pada hak dan kewajiban reparatoris transisional setelah berlalunya waktu? Intuisi kita menganggap bahwa klaim-klaim tersebut akan menjadi 67 Lihat Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation, Stanford: Stanford University Press, 1991. 68 Lihat misalnya Legal Rehabilitation Law, No. 119/1990 (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1990); Law on Political and Civil Rehabilitation of Oppressed Persons (Bulgaria, 1991); Law on Former Victims of Persecution, No. 7748 (Albania, 1993); Legislative Decree No. 118 (Romania, 1990); Law on the Rehabilitation of Victims of Political Repression (Rusia, 1991). 69 Lihar Russian Press Digest, 19 Agustus 1992, hal. 91. Lihat juga Current Digest of the Post-Soviet Press, 2 September 1992. 70 Lihat misalnya Law on the Rehabilitation of Victims of Political Repression (Rusia, 1991), Pasal 12: “Individu yang direhabilitasi berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang ini dikembalikan hak-hak sosial politis, sipil, militer dan gelar-gelar khususnya, yang hilang sebagai akibat penindasan, dan penghargaan serta medali mereka yang dikembalikan”. Pasal 15 menyatakan: “Individu yang mengalami tindakan penindasan dalam bentuk pencabutan kebebasan dan direhabilitasi berdasarkan undang-undang ini ... mendapatkan kompensasi moneter sebesar 180 rubel untuk tiap bulan penahannya ....” 71 Lihat “Presidential Decree on Rehabilitation of the Cossacks”, British Broadcasting Corporation, 29 Juni 1992; “Crimean Tatar Village Rehabilitated after 48 Years”, British Broadcasting Corporation, 2 November 1992. 72 “Jutaan orang ... ditindas karena agama, status sosial, nasional atau lainnya ... Parlemen Rusia menyampaikan belasungkawanya terhadap para korban ... dan menganggap ‘pembersihan’ tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan menyatakan keinginan tegas untuk menjalankan hukum dan hak-hak sipil.” Lihat catatan kaki 70 di atas. 23 lemah setelah waktu berlalu.73 Jeremy Waldron, dalam menyusun teori tentang intuisi umum tentang ketidakadilan dalam perjalanan waktu, menyatakan bahwa ketidakadilan akan “terlewati”, hak-hak akan melemah, dengan munculnya kondisi baru yang menggantikan ketidakadilan di masa lalu.74 Namun intuisi demikian tampaknya tidak tepat dalam masa transisi; karena banyak proyek reparatoris yang dibicarakan dalam bab ini dilaksanakan lama setelah terjadinya penindasan negara dan sering kali setelah jangka waktu yang cukup panjang. Konsekuensi waktu di sini tampaknya tidak sesuai dengan intuisi kita. Bahkan, seperti ditunjukkan oleh beberapa kasus, dilema transisional dapat dihindari dengan menunda pelaksanaan keadilan. Misalnya, setengah abad setelah terjadinya kekejaman masa Perang Dunia Kedua, para korban atau ahli warisnya tetap mendapatkan penggantian kerugian. Usaha reparatoris di bekas blok Soviet juga dilaksanakan setelah jangka waktu yang panjang. Setelah perang dan pendudukan yang berkepanjangan, penggantian kerugian transisional sering kali ditunda untuk waktu yang lama; namun praktik-praktik tersebut tidaklah melemah seiring perjalanan waktu. Pengalaman yang dibicarakan dalam bab ini (dan di seluruh buku ini) menunjukkan bahwa waktu berpengaruh secara paradoksal terhadap penggantian kerugian transisional; dan terlebih lagi, alasan utamanya adalah peran penindasan negara yang belum dianalisis. Bila pelaku utama pelanggaran adalah negara, berjalannya waktu memiliki konsekuensi yang tidak terbayangkan bagi keadilan transisional. Waktu mempengaruhi perjalanan politik dengan dampak terhadap prasyarat keadilan, namun intuisi umum tidak bisa menjelaskan dampaknya bagi hak-hak reparatoris para korban, selain kewajiban negara untuk, membayarkan kompensasi – konsekuensi yang sekali lagi menggarisbawahi ciri utama pembeda keadilan korektif secara abstrak dengan keadilan reparatoris dalam kondisi transisional. Ciri utamanya adalah peran negara dalam kejahatan di masa lalu dan dampaknya bagi kemungkinan perbaikan. Dalam kondisi ini, peran waktu justru paradoksal. Perjalanan waktu dapat memfasilitasi penentuan faktafakta pelanggaran di masa lalu, selain memberikan jarak politik yang lebih jauh dari rezim pendahulu, dan memberikan akses lebih besar terhadap arsip negara. Terlebih lagi, semakin banyak dokumentasi yang ada akan berakibat pada semakin mungkinnya diberikan kompensasi, meskipun perjalanan waktu bisa pula berakibat pada mortalitas mereka yang seharusnya mendapatkan kompensasi. Namun, dalam kondisi demikian, ganti rugi diberikan kepada ahli waris, keturunan dan bahkan wakil-wakil para korban. Seiring perjalanan waktu, dilema proyek reparatoris transisional yang ditunda menimbulkan masalah keadilan antar-generasi. Dalam keadilan korektif konvensional, korban mendapat penggantian dari para pelanggar, dan bahkan bila bukan dari pelanggar yang diidentifikasi, dari generasi politik para pelanggar; dalam proyek reparatoris transisional, ganti rugi bagi para korban diberikan dari anggaran pemerintah pusat. Berjalannya waktu menimbulkan perubahan identitas tidak saja para penerima ganti rugi, namun juga mereka yang memberikan ganti rugi. Timbul masalah karena mereka yang membayar untuk kesalahan di masa lalu seharusnya secara pribadi tidak terkait dengan 73 Untuk analisis yang mendalam, lihat Jeremy Waldron, “Superseding Historic Injustice”, Ethics 103 (1992): 4-28 dan George Sher, “Ancient Wrongs and Modern Rights”, Philosophy and Public Affairs 10, No. 1 (1980): 3, 6-7. Lihat juga Derek Parfit, Reasons and Persons, New York: Oxford University Press, 1989. 74 Lihat Waldron, “Superseding Historic Injustice”, 4-28. 24 pelanggaran di masa lalu. Apakah adil bahwa generasi di masa depan harus membayar kesalahan rezim di masa yang telah lama berlalu? Pertanyaan ini menimbulkan masalah keadilan antar-generasi yang signifikan. Secara umum, masalah utama keadilan antar-generasi adalah tentang adil-tidaknya generasi masa kini berkorban untuk generasi mendatang. Seperempat abad lalu, John Rawls menunjukkan masalah itu: “Seberapa lebih baik kita inginkan generasi mendatang?”75 Namun, belakangan ini, pertanyaan tentang keadilan lintas generasi ini dipertanyakan kembali dan gambaran tentang masa depan yang tidak terlalu cerah mulai terlihat. Arah perhatian tentang sumber daya masyarakat di masa depan tidak lagi berfokus masalah akumulasi, melainkan degradasi. Pertanyaan tentang keadilan lintas generasi diformulasikan ulang.76 Problem transisional yang dikemukakan di sini menjelaskan dimensi lain dari permasalahan keadilan lintas generasi. Keadilan reparatoris yang dilaksanakan setelah berjalannya waktu menimbulkan pertanyaan antar-generasi tentang kewajiban apa yang ditanggung rezim penerus kepada korban dari generasi pendahulu. Dan apakah adil untuk membebankan tanggung jawab ini kepada generasi masa kini atau sesudahnya. Adil-tidaknya reparasi setelah berlalunya waktu merupakan pertanyaan penting bagi masyarakat transisional yang berkutat dengan kewajiban itu. Preseden yang dibahas di sini menjelaskan apa yang menjustifikasi penanggungan beban tanggung jawab oleh rezim penerus setelah berlalunya waktu, yang menjelaskan apa yang merupakan pertimbangan utama untuk menyikapi sejarah pelanggaran di suatu negara. Sebagai contoh, skema reparatoris kontemporer yang ditujukan untuk memperbaiki ketidakadilan era Stalin menunjukkan dilema berlalunya waktu, karena skema tersebut mendapat tentangan. Skema ini ditentang karena merupakan kasus di mana satu generasi harus membayar kerugian generasi yang lain dan dijustifikasikan secara umum atas pertimbangan moral.77 Dalam contoh lain, lebih dari setengah abad setelah berlalunya perang, di Jerman, sejarah pelanggaran negara ini masih dianggap sebagai “defisit moral” negara.78 Pertanyaannya menjadi apakah sejarah moral ini dapat dan harus diwariskan. Intuisi ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, meskipun tampaknya tidak ada pelanggaran pribadi, dalam generasi penerus, tetap ada anggapan bahwa generasi penerus mewarisi kebijakan yang buruk dari rezim pendahulunya, yang menyebabkan mereka mendapat keuntungan yang bukan haknya. Satu cara lain untuk berpikir tentang hal ini adalah bila generasi sebelumnya menghambur-hamburkan sumber daya moral nasional yang ada, timbul defisit yang diwariskan kepada generasi sesudahnya, yang pada akhirnya harus menanggung hutang itu. Masyarakat dalam transisi yang sedang mempertimbangkan skema reparatoris setelah jangka waktu yang lama mencerminkan pemahaman defisit moral demikian. Perdebatan tentang apakah tindakan reparatoris dapat dijustifikasi menganggap masalah keadilan reparatoris transisional lintas generasi sebagai suatu hal yang 75 Lihat John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1971. Untuk diskusi lebih luas tentang masalah keadilan lintas generasi, lihat Brian Barry, Theories of Justice, Berkley: University of California Press, 1989, 189-94. 77 Untuk kritik umum tentang skema-skema ini, lihat András Sajó, “Preferred Generations: A Paradox of Counter Revolutionary Constitutions”, Cardozo Law Review 14 (1993): 847. 78 Sagi, German Reparations, 62-72 (membicarakan pembicaraan Kanselir Konrad Adenauer yang menjustifikasi kewajiban Jerman untuk memberikan reparasi, mengutip K. Grossman, German’s Moral Debt, The German-Israel Agreement). 76 25 melibatkan pewarisan “defisit” dalam sumber daya moral suatu bangsa. Bahasa moral demikianlah yang menjustifikasi reparasi dalam pertimbangan tentang pembayaran Jerman berkaitan dengan kejahatan perang terhadap para korban penindasan Nazi.79 Pembayaran reparasi tampak sebagai usaha untuk meningkatkan kapital moral. Serupa dengan itu, dalam skema penggantian kerugian Amerika Latin, tujuan reparasi mencakup pengembalian kredibilitas moral negara.80 Bahasa serupa yang penuh pertimbangan moral tampak dalam kebijakan reparatoris lainnya, seperti dalam skema kompensasi Amerika kepada warga keturunan Jepang yang ditahan selama Perang Dunia Kedua. Hampir setengah abad setelah pelanggaran besar-besaran terhadap hak sipil dan kebebasan oleh pemerintah di masa perang, sebuah komisi penyelidikan menyimpulkan bahwa prasangka rasial, dan buka keamanan militer, yang menjadi dasar penahanan tersebut dan menyarankan permintaan maaf resmi dan reparasi oleh pemerintah.81 Japanese Civil Liberties Act tahun 1988 secara formal mengakui ketidakadilan terhadap warga keturunan Jepang tersebut selama Perang Dunia Kedua dan memberikan kompensasi kepada individu-individu yang ditahan.82 Pada tahun 1990, empat puluh delapan tahun setelah perintah Presiden Franklin Roosevelt yang diskriminatif tersebut, Presiden George Bush secara resmi meminta maaf atas nama negara.83 Restorasi moral negara dijadikan alasan untuk reparasi tersebut oleh Kongres. Setelah berlalunya waktu, tindakan reparatoris semakin bersifat simbolis; sering kali mengambil bentuk permintaan maaf, yang tergambar dalam respon terhadap pelanggaran masa perang di atas. Permintaan maaf juga terlihat dalam respon lain terhadap kejahatan sejarah, seperti perbudakan dan segregasi. Dengan berjalannya waktu, kerugian yang ditimbulkan lebih pada reputasi di mata publik, dan dengan demikian dapat diperbaiki dengan permintaan maaf politis. Setelah berjalannya waktu, keadilan transisional sering kali mengambil bentuk ini. Meskipun teori umum menganggap bahwa permintaan maaf lebih merupakan fungsi kebudayaan,84 pengalaman yang dilihat di sini menunjukkan faktor lain yang mungkin lebih penting, yaitu kaitan antara keadilan transisional dengan berlalunya wakltu. Perhatian terus menerus pada moral menggarisbawahi kekuatan peninggalan sejarah yang buruk sebagai tantangan terhadap legitimasi negara-negara yang menuju liberalisasi. perhatian ini sebagian bisa menjelaskan mengapa generasi penerus memikul beban berat tanggung jawab dari masa lalu. Meskipun pelanggaran dan liabilitas semula ditimbulkan oleh generasi pendahulu, peninggalan buruk tersebut menjadi perhatian 79 Sagi, German Reparations, 66. Lihat Laporan Kebenaran dan Rekonsiliasi Cili, 13. 81 Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, Personal Justice Denied: Report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, Washington, D.C.: Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, 1982, 6-9. 82 War and National Defence Restitution for World War II Internment of Japanese-American and Aleuts, U.S. Code, Vol. 50, sec. 1989 (membentuk Civil Liberties Public Education Funs) (1988). Untuk diskusi tentang gerakan untuk memperoleh reparasi dan dampak hukum tersebut, lihat Sarah L. Brew, “Making Amends for History: Legislative Reparations for Japanese Americans and Other Minority Groups”, Law and Inequality 8.1 (1989): 179. Lihat juga Peter Irons, Justice at War, Berkley: University of California Press, 1993. 83 Lihat “First Payments Are Made to Japanese World War II Interness”, New York Times, 10 Oktober 1990, hlm. A21 (pembayaran reparasi disertai surat permintaan maaf dari Presiden Bush atas nama seluruh negara). 84 Lihat misalnya Tavuchis, Mea Culpa. 80 26 seluruh masyarakat untuk seterusnya, sering kali dengan dampak buruk bagi generasi kini dan mendatang. Dalam pertimbangan peradilan pidana, konsepsi tanggung jawab koletif yang serupa juga muncul dalam masa transisi. Bila tidak diselesaikan, perasaan ketidakadilan akan semakin tinggi. Terlebih lagi, setelah perjalanan waktu, tindakan reparatoris menjadi simbol transisi dan bisa digunakan untuk memantapkan keberhasilankeberhasilan dalam transisi menuju demokrasi. Pemikulan tanggung jawab rezim lama oleh rezim baru menunjukkan bagaimana pemikulan tanggung jawab kolektif menyusun identitas politik suatu negara seiring perjalanan waktu. Persistensi Keadilan Reparatoris yang Kontemporer: Dilema “Affirmative Action” Belum Terselesaikan dan Politik Dengan berlalunya waktu, proyek reparatoris bergeser semakin jauh dari model tradisional keadilan korektif. Setelah waktu berlalu, para pelaku pelanggaran tidak membayar; mereka yang tidak bersalah harus melakukannya. Dan setelah berlalunya waktu, ganti rugi tidak diberikan kepada para korban, namun kepada para keturunan mereka. Dengan berjalannya waktu, skema reparatoris menjadi tidak mirip lagi dengan keadilan korektif konvensional dan semakin menyerupai distribusi sosial dan masalah politis. Kebijakan reparasi yang tidak diarahkan pada korban-korban yang tidak teridentifikasi namun kepada kelompok perwakilan korban yang diidentifikasi berdasarkan penindasan di masa lalu tampak seperti skema distribusi. Skema distribusi demikian bersifat kontroversial, karena alokasi demikian tampaknya bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal dan kedaulatan hukum. Sebagai contoh, yang sedang hangat dibincangkan adalah adil tidaknya alokasi tunjangan publik dan privat berdasarkan garis rasial di Amerika Serikat – isu “affirmative action”. Pertimbangkanlah kontroversi kontemporer tentang affirmative action berdasarkan ras sebagai masalah keadilan reparatoris transisional yang belum terselesaikan. Penindasan resmi terhadap warga keturunan Afrika di Amerika Serikat dilakukan selama berabad-abad, pertama, melalui toleransi pemerintah terhadap perbudakan, dan kemudian melalui segregasi secara resmi. Setelah Perang Saudara, terdapat usulan reparasi, yang paling terkenal adalah “empat puluh are tanah dan seekor keledai”.85 Namun, hingga saat ini, bahkan tidak ada pengakuan resmi bahwa negara melakukan kesalahan atau reparasi untuk pelanggaran hak, meskipun pertanyaan ini tetap menjadi bagian dari kontroversi dan perdebatan kontemporer.86 Terdapat seruan agar pemerintah meminta maaf, seperti dibicarakan di muka, yang bisa berfungsi sebagai reparasi simbolis. Terdapat pula perdebatan tentang upaya hukum atau remedi affirmative 85 Untuk tinjauan historis, lihat Eric Foner, Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863-1877, New York: Harper Collins, 1989. Untuk analisis kontemporer, lihat Jed Rubenfeld, “Affirmative Action”, Yale Law Journal 107 (1977): 427 (membicarakan berbagai tindakan yang eksplisit ras setelah masa Perang Saudara, seperti Act of July 28, 1866); Treaties and Proclamations of the United States of America, U.S. Statutes at Large 14 (1868): 310. Lihat juga William Darity, Jr., “Forty Acres and a Mule: Placing a Price Tag on Oppression”, dalam The Wealth of Races: The Present Value from Past Injustices, ed. Richard F. America, New York: Greenwood Publishing Group, 1990: 3-13. 86 Untuk elaborasi tentang reparasi bagi warga keturunan Afrika, lihat Boris I. Bittker, The Case for Black Reparations, New York: Random House, 1973; untuk diskusi tentang perdebatan politik yang berlanjut, lihat Brent Staples, “Forty Acres and a Mule”, New York Times, 21 July 1977, editorial. 27 action, misalnya, apakah pemberian tunjangan pemerintah berdasarkan ras bisa dijustifikasi untuk menjadi remedi diskriminasi resmi di masa lalu.87 Dalam pendekatan yang umum, isu affirmative action pada umumnya ditempatkan dalam kerangka masalah keadilan korektif konvensional. Remedi yang sensitif-ras dijustifikasi hanya sejauh mereka yang telah mengalami kerugian karena ras mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari mereka yang telah merugikan mereka. Pendekatan konstitusional yang berlaku kini menempatkan hak sebagai sesuatu yang timbul dari kerugian; jadi, pasti terdapat efek berlanjut dari diskriminasi rasial resmi di masa lalu, dan seperti dalam keadilan korektif tradisional, kaitan dengan entitas yang melakukan tindakan perbaikan.88 Dalam pendekatan yang umum, harus ada temuan yang spesifik yang mengaitkan entitas pemerintahan yang melakukan skema remedial ini dengan diskriminasi di masa lalu; pelaku pelanggaranlah yang harus membayar.89 Namun, setelah berjalannya waktu, analogi affirmative action dengan keadilan korektif konvensional menjadi tidak tepat. Para pelaku “asli” telah meninggal, demikian pula para korban “asli”. Lalu bagaimana menyikapi hal-hal yang tersisa? Ini adalah peninggalan penindasan politik yang tidak diselesaikan, suatu masalah keadilan reparatoris yang belum terselesaikan. Mari kita pikirkan kembali masalah yang ditimbulkan affirmative action, dengan dipandu preseden dan prinsip transisional. Pelbagai pengalaman yang dibidik dalam bab ini menunjukkan bahwa pemerintah penerus sering kali menjalankan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi bagi korban-korban penindasan oleh rezim pendahulu, dan kewajiban tersebut terus ditanggung meskipun waktu terus berjalan. Di bekas blok Soviet, ganti rugi diberikan hampir setengah abad setelah pelanggaran era Stalin tersebut terjadi. Sementara pendekatan umum terhadap affirmative action dijustifikasi berdasarkan kerugian atau dampak penindasan yang terus berpengaruh, keadilan transisional tidak harus tergantung pada hal itu. Setelah berlangsungnya waktu, sementara pihak-pihak yang mengalami penindasan secara langsung mungkin sudah melupakan masa lalu, masyarakat secara keseluruhan masih merasakan adanya pelanggaran yang tidak dipulihkan itu. Persistensinya isu politik dan pelaksanaan tindakan reparatoris setelah jangka waktu yang panjang menunjukkan pengakuan negara dan pemikulannya terhadap tanggung jawab untuk memperbaiki dosa politik yang dilakukan oleh rezim pendahulunya. Dari preseden tersebut timbul konsepsi baru tentang keadilan reparatoris transisional yang dicirikan oleh peninggalan sejarah. Bila negara telah menganiaya warganya sendiri atas dasar ras, etnik, agama atau politik, kebutuhan untuk perbaikan sesuai dengan kedaulatan hukum dan transformasi politik tidak hilang hanya karena waktu. Sementara dalam sebagian besar contoh di atas, reparasi dilakukan oleh rezim pertama yang menggantikan rezim pelaku pelanggaran, di Amerika Serikat, pertanyaan ini menjadi masalah berbagai pemerintahan penerus. Satu contoh adalah perlakuan 87 Untuk analisis mendalam, lihat Michel Rosenfeld, Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry, New Haven: Yale University Press, 1991; Rubenfeld, “Affirmative Action”. 88 Untuk versi awal tentang pandangan ini, lihat Bakke vs. Regents of University of California, 438 US 265, 324 (1978). Untuk pernyataan lebih kontemporer, lihat Richmond vs. Croson, 488 US 469 (1989); lihat juga Adarand Construction Inc. vs. Pena, 515 US 200 (1995). 89 Kathlen M. Sullivan, “Sins of Discrimination: Last Term’s Affirmative Action Cases”, Harvard Law Review 100 (1986): 78 (menyatakan bahwa fokus pengadilan pada pelaku individual mencegahnya menerima justifikasi lain untuk program affirmative action) 28 terhadap warga pribumi Amerika setelah Perang Dunia Kedua.90 Skema reparatoris dilakukan secara tidak terpola, meskipun paling tidak ada semacam pengakuan resmi terhadap kesalahan di masa lalu. Reparasi terhadap penahanan warga keturunan Jepang pada masa perang dilakukan secara lebih komprehensif. Dalam kasus ini, reparasi dilakukan sebagai kewajiban nasional, meskipun pelanggaran telah lama berlalu. Hak untuk mendapatkan ganti rugi timbul dari pengakuan pemerintah terhadap pelanggaran yang hingga sebelumnya tidak diakui dan tidak diperbaiki. Pertanyaan konvensional tentang affirmative action, seperti apakah penindasan tersebut memiliki “dampak berlanjut”, bahkan tidak ditanyakan. Namun, dampak stigmatisasi psikologis dianggap timbul dari diskriminasi yang disponsori negara dan dari kelalaian pemerintahan penerus untuk memberikan remedi. Seperti dalam preseden transisional lainnya yang dibicarakan dalam bab ini (tentang penghilangan), kelalaian pemerintahan penerus untuk merespon dengan sendirinya dianggap merupakan bagian dari keberlanjutan pelanggaran. Jika penahanan warga keturunan Jepang selama waktu relatif pendek ini dianggap merupakan penindasan etnik yang berkelanjutan, apalagi diskriminasi, perbudakan dan segregasi terhadap warga keturunan Afrika. Praktik, prinsip dan nilai-nilai transisional yang dibicarakan dalam bab ini bisa menerangkan dan memandu skema affirmative action kontemporer.91 Mungkin ciri paling kontroversial dari praktik reparatoris setelah suatu jangka waktu adalah pemberian tunjangan, bukan kepada korban sebenarnya, namun kepada keturunan dan wakilwakilnya. Di sini, praktik transisional memiliki pengalaman komparatif serupa. Banyak skema pasca-Soviet yang dijalankan lebih dari 40 tahun setelah terjadinya penindasan politik mempertimbangkan pemberian hak kepada para pewaris korban-korban semula. Undang-Undang Ceko secara jelas mengakui klaim dari cucu para korban semula – selisih dua generasi dari korban asli.92 Mungkin contoh terbaik adalah skema reparatoris Jerman pasca-Perang Dunia Kedua, yang memberikan reparasi untuk melakukan remedi terhadap penindasan di masa lalu, meskipun faktanya banyak dari korban yang seluruh keluarganya sama sekali dimusnahkan, sehingga tidak ada pewaris yang bisa menerima ganti rugi. Preseden reparasi Jerman ini menunjukkan bahwa hak-hak korban bisa diwariskan kepada badan perwakilan khusus yang dibentuk untuk keperluan ini.93 Preseden sejarah ini mencerminkan praktik yang dalam buku ini diistilahkan sebagai “reparasi perwakilan”, yang diberikan oleh pemerintahan penerus kepada kelas penerus korban, untuk memperbaiki pelanggaran negara di masa lalu. Pengakuan signifikansi reparasi perwakilan bisa membantu menjelaskan persistensi affirmative action dan kontroversi serupa, meskipun waktu telah lama berjalan. Reparasi perwakilan menandakan bahwa hal yang menjustifikasi pemikulan tanggung jawab reparatoris oleh pemerintah penerus bahkan setelah jangka waktu yang lama adalah penindasan negara yang tidak diakui dan tidak diperbaiki, yang merupakan ancaman berlanjut bagi kedaulatan hukum. Preseden reparatoris transisional dalam berbagai budaya hukum 90 Lihat Nell Jessup Newton, “Compensation, Reparations and Restitution: Indian Property Claims in the United States”, Georgia Law Review 28 (musim dingin 1994): 453. 91 Mari J. Matsuda, “Looking to the Bottom: Critical Legal Studies and Reparations”, Harvard Civil RightsCivil Liberties Law Review 22 (musim semi 1987): 323. 92 Law on Extrajudicial Rehabilitation, bag. 3, paragraf 2. 93 Negara Israel maupun Konferensi Klaim merupakan badan perwakilan demikian, dan keduanya menerima pembayaran. Lihat Honig, “Reparations Agreement”, 567. 29 menunjukkan realitas inti: peninggalan sejarah penindasan negara tidak bisa menghilang dengan sendirinya, meskipun sering kali penyelesaiannya ditunda. Dilema Transitory Tort Apa yang terjadi dengan keadilan reparatoris bila negara tidak mengakui hak-hak demikian? Ke mana perginya hak-hak tersebut? Apakah pemenuhannya terikat dengan rezim penerus, atau bisa dipenuhi oleh pihak lainnya? Sejumlah kasus di Amerika Serikat tentang “pelanggaran berat” hak asasi manusia menunjukkan bahwa dalam kasus penindasan yang paling buruk, pemenuhan hak korban tidak terbatas oleh batas negara yang terkait. Ini sering kali terlihat pada awal transisi, ketika mereka yang terlibat dalam pelanggaran di masa sebelumnya sering kali melarikan diri. Ketika rezim berkuasa di Paraguay menolak bertanggung-jawab atas tewasnya Joel Filartiga karena penyiksaan, keluarga korban mencari keadilan hingga ke Amerika Serikat, di mana pelakunya mantan kepala polisi Paraguay, melarikan diri. Dalam suatu kasus yang kemudian menjadi preseden penting bagi korban pelanggaran negara untuk memperoleh hak-haknya di pengadilan Amerika, keluarga korban menggunakan hukum berusia dua abad, Alien Tort Act, yang berasal dari masa pembentukan negara itu, yang memberikan jurisdiksi kepada Amerika Serikat untuk mengadili warga negara asing dalam kasus pelanggaran terhadap “hukum bangsa-bangsa”.94 Dipandu dengan analogi terhadap pembajakan, pengadilan banding menyatakan bahwa “penyiksaan oleh negara” merupakan pelanggaran terhadap “hukum bangsa-bangsa”, dan dengan demikian tuntutan ini dapat diadili di pengadilan mana pun.95 “Untuk keperluan tanggung jawab perdata, penyiksa tersebut – seperti bajak laut dan pedagang budak sebelumnya – dianggap sebagai hostis humani generis, musuh seluruh umat manusia”.96 Klaim kompensatoris yang berasal dari hak-hak yang dilindungi “hukum bangsa-bangsa” secara tradisional dianggap sebagai penyebab tindakan transitoris, yang dapat diadili di mana pun. Penyiksaan secara sengaja, seperti pembajakan, melanggar hukum bangsa-bangsa; dengan demikian, hak untuk mendapatkan reparasi dari penyiksaan negara harus diperlakukan sebagai klaim transitoris. Kasus Joel Filartiga dilanjutkan dengan sejumlah besar kasus-kasus alien tort lainnya, biasanya tentang penyiksaan negara atau eksekusi di luar hukum. Dalam kasus Forti dan Siderman, tuntutan diajukan kepada penyiksa Argentina yang ditemukan di Amerika Serikat. Tindakan penyiksaan yang merupakan tanggung jawab Argentina dianggap melanggar norma-norma “jus cogens”, norma-norma kuat dalam hukum internasional yang tidak bisa diabaikan dan memiliki keberlakuan dan perlindungan yang universal.97 Kasus in re Estate of Marcos berkaitan dengan penyiksaan di Filipina, yang 94 Lihat Judiciary Act of 1789, U.S. Code, vol. 28, bag. 1350 (1993). Filartiga vs. Pena-Irala, 630 F2d 876, 890 (2d Cir 1980) (menyatakan bahwa penyiksaan resmi melanggar “norma-norma yang telah mapan dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan dengan demikian juga hukum bangsa-bangsa”). 96 Ibid., 884-87. Lihat umumnya Ian Brownlie, Principles of Public International Law, edisi keempat, New York: Oxford University Press, 1990, 238-39 (tentang hukum internasional di laut lepas). 97 Forti vs. Suarez-Mason, 672 F Supp 1531 (1987); Siderman de Blake vs. Argentina, 965 F2d 699 (9th Cir 1992). 95 30 diajukan terhadap Ferdinand Marcos, mantan presiden.98 Dalam semua kasus tersebut, para korban atau keluarganya mengajukan tuntutan kepada para pelaku di Amerika Serikat. Prinsip jurisdiksional yang mengikutinya adalah bahwa dalam kasus penindasan politik, liabilitas perdata bersifat transitoris dan mengikuti pelaku. Preseden Alien Tort Act ini, dengan dipandu analogi terhadap pembajakan, bergantung pada fiksi hukum tentang pelanggar hukum individual dan pemikiran keadilan korektif yang tradisional, di mana liabilitas perdata mengikuti pelaku tunggal. Mungkin kasus ekstrem dalam hal ini adalah tuntutan alien tort terbaru terhadap Radovan Karadzic, pemimpin politik Serbia Bosnia, yang dituntut pertanggungjawaban perdatanya terhadap ribuan kekejaman yang dilakukan sesuai kebijakan penindasan etnik di daerah Balkan.99 Konsepsi utama transitory tort, yaitu bahwa liabilitas mengikuti tortfeasor (pelaku), bersifat paradoksal. Di mana letak kesalahan? Dalam kasus penyiksaan yang dilakukan biasanya berdasar hukum negara – yang didorong atau dibiarkan negara – siapa yang harus bertanggung-jawab? Sejauh mana klaim reparatoris yang terkait transisi akibat penindasan negara modern dapat dibebankan kepada pelaku pelanggaran individual?100 Hingga satu titik, alien tortfeasor merupakan konstruksi juridis yang paling bisa dipahami sebagai semacam resolusi pragmatik dari keadilan dalam kondisi yang tidak ideal. Bila rezim bertanggung-jawab, ia tidak bisa dituntut di pengadilan domestik negara yang bersangkutan.101 Lebih lanjut lagi, pemerintah asing umumnya kebal dari tuntutan di pengadilan Amerika karena alasan imunitas kedaulatan. Hal yang praktis adalah untuk menggunakan konsep liabilitas perdata tradisional. Namun paradoks penggunaan alien tort untuk perbaikan kesalahan yang terkait hak asasi manusia adalah bahwa sementara penyebab respon adalah tindakan individual, ia juga mengakui latar belakang kebijakan negara. Meskipun Alien Tort Act menjadi alasan untuk menindak pelaku individual, jurisdiksinya didasarkan pada pelanggaran “resmi” yang dilakukan berdasar hukum negara. Hanya sejumlah kecil pelanggar memenuhi syarat ini, dan tindakan mereka jelas telah melanggar hukum bangsa-bangsa. Pada saat yang sama, klaim tersebut jelas mengabaikan imunitas kedaulatan, yaitu kekebalan negara-negara asing dari jurisdiksi, dengan pengecualian tertentu. Pelanggaran yang memiliki konsensus paling besar adalah penyiksaan, eksekusi di luar hukum dan genosida,102 yang dianggap sebagai norma “jus 98 In re Restate of ferdinand Marcos, 25 F3d 1467 (9th Cir 1994). Kadic vs. Kardzic; Doe vs. Karadzic, 70 F3d 232 (2d Cir 1995). 100 Perdebatan tentang apa yang dalam buku ini disebut “transitory torts” menurut hukum kebiasaan internasional, lihat Curtis A. Bradley dan Jack L. Goldsmith, “Customary International Law as Federal Common Law: A Critique of the Modern Position”, Harvard Law Review 110 (Februari 1997): 815 (menyatakan bahwa hukum internasional seharusnya tidak diberikan status seperti common law federal); Harold Hongju Koh, “Commentary: Is International Law Really State Law?” Harvard Law Review 111 (1998): 1824. Lihat juga Ryan Goodman dan Derek P. Jinks, “Filartiga’s Firm Footing: International Human Rights and Federal Common Law”, Fordham Law Review 66 (1977): 463. 101 Lihat Argentine Republic vs. Amerada Hess Shipping Corp, 488 US 428 (1989). Namun lihat Siderman de Blake, 965 F2d 699. 102 Filartiga, 630 F2d 876. 99 31 cogens” dengan status tertinggi dalam hukum internasional, dengan latar belakang kebijakan negara atau yang serupa.103 Hampir dua dekade setelah persidangan kasus penting Filartiga itu, dan juga selama masa persidangannya, terdapat banyak keputusan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus bertanggung-jawab. Bahkan, remedi tersebut diratifikasi menjadi hukum federal: Torture Victims Protection Act mengizinkan penindakan perdata untuk mendapatkan ganti rugi keuangan terhadap pelanggaran seperti penyiksaan oleh negara dan eksekusi di luar hukum bila pelaku berada dalam jurisdiksi.104 Selama bertahun-tahun, telah lebih banyak keputusan daripada pembayaran.105 Pengakuan tanggung jawab perdata memiliki dampak yang lebih luas dari pemberian ganti rugi keuangan. Dalam kasus demikian, liabilitas perdata memiliki sanksi publik karena perhatian media terhadap proses perdata yang melibatkan pejabat tinggi negara asing. Dampak publisitas seperti ini sedemikian besar sehingga selama masa persidangan, para terdakwa sering kali melarikan diri. Liabilitas individual, meskipun bersifat perdata, berakibat pada stigma dan sanksi sosial serupa dengan sanksi pidana. Banyaknya usaha pencarian keadilan reparatoris lintas batas negara, seperti juga usaha serupa setelah jangka waktu yang panjang, menunjukkan peran kompleks dan dinamis remedi demikian. Meskipun remedi perdata biasanya diambil untuk memberikan hak-hak korban, seperti tindakan transisional lain yang dibicarakan di muka, tuntutan alien tort memiliki kegunaan lain yang biasanya dikaitkan dengan sanksi pidana, seperti pengakuan kesalahan pemerintah dan eksklusi pelaku dari komunitas. Bahkan, transitory tort menerangkan kaitan antara pengembalian hak-hak korban, pengakuan kesalahan individual dan penindasan oleh negara. Timbulnya transitory tort dalam kasus penindasan menunjukkan konsep keadilan reparatoris memiliki keserupaan dengan respon-respon hukum transisional lainnya. Dalam memediasi kepentingan berbeda antara publik dan privat, individu dan kolektif, nasional dan internasional, alien tort secara efektif merespon pelanggaran penindasan yang merupakan ciri utama represi modern. Seperti “kejahatan terhadap kemanusiaan”, transitory tort terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjelasan konsepsi yang serupa: sumber tindakan hukum yang melampaui jurisdiksi waktu dan tempat, yang digambarkan sebagai “tort terhadap kemanusiaan”. Tort ini merupakan respon terhadap penindasan oleh negara pada masa kontemporer, dalam sumber tindakan hukum terhadap individu yang terkait dalam kebijakan penindasan yang lebih luas. Terlebih lagi, tort terhadap kemanusiaan menantang intuisi umum di mana penyebab tindakan perdata berkaitan dengan jurisdiksi tertentu, yang tidak tepat untuk menangkap pelanggaran berat yang dilakukan negara. Dengan ketiadaan parameter jurisdiksional yang biasa, yang “asing” dijadikan “domestik”, dan pelanggaran internasional didefinisikan ulang. Dan meskipun dicapai di luar sistem hukum nasional, dengan mengakui hak-hak para korban, tindakan-tindakan seperti itu dapat mengawali proses 103 Lihat The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, U.S. Code, Vol. 28, bag. 1602-1611 (1994). Kadang-kadang jurisdiksi diambil terhadap pelanggaran lain, seperti penghilangan dan penahanan secara sewenang-wenang yang berkepanjangan. Lihat Forti, 672 F Supp 1541-42. 104 Torture Victims Protection Act of 1991, U.S. Code, Vol. 28, bag. 1350 (1993). 105 Lihat Siderman de Blake, 965 F2d 699; In Re Estate of Ferdinand Marcos, 25 F3d 1467. Lihat umumnya Ralph Steinhardt, “Fulfilling the Promise of Filartiga: Litigating Human Rights Claims against the Estate of Ferdinand Marcos”, Yale Law journal of International Law 20 (1995): 65. 32 transisi. Bahkan bila rezim belum berganti dan tidak ada perubahan politik, penegasan norma-norma utama hak asasi manusia dapat berperan konstruktif. Respon legal transisional ini mendorong munculnya pendekatan yang fleksibel terhadap kedaulatan dan jurisdiksi. Pergeseran dari prinsip konvensional ini dirasionalkan dengan memandang pada tindakan negara dan sejauh mana ia menaati kedaulatan hukum masyarakat internasional. Keadilan Reparatoris Transisional Praktik-praktik yang dibicarakan di muka menunjukkan paradigma keadilan reparatoris yang dikaitkan dengan masa transisi. Paradigma keadilan reparatoris transisional merupakan konsepsi yang kompleks, karena ia memajukan berbagai tujuan yang memediasi dan mengkonstruksi transisi. Reparasi transisional secara terbuka mengakui dan memberikan hak-hak individual yang pada dasarnya bersifat simbolik. Sering kali tidak diberikan kompensasi sepenuhnya, dan tidak ada kaitan dengan kerugian meterial, seperti dalam “reparasi moral” Amerika Latin atau rehabilitasi pasca-komunis. Reparasi transisional memiliki berbagai bentuk: bisa berbentuk restitusi properti, pembayaran keuangan, atau kompensasi yang tidak konvensional, seperti keringanan biaya pendidikan atau penyediaan pelayanan dan keuntungan publik lainnya, seperti monumen, rehabilitasi secara hukum dan pemaafan. Paradigma reparatoris transisional berbeda dari intuisi kita yang berlaku selama ini tentang keadilan korektif dalam sejumlah karakter.106 Konsepsi transisional memiliki kekurangan dalam hal simetri soal sistem tort privat, karena ia memahami ulang relasi antara korban dengan pelaku kekerasan, antara individu dengan kolektif.107 Sementara dalam pemahaman yang berlaku selama ini, pemulihan bagi para korban dilimpahkan kepada para pelaku, maka pemikiran reparatoris transisional menyediakan pengakuan resmi tentang hak-hak para korban dan tanpa perlu menempatkan kesalahan atau pelanggaran secara individual. Yang menentukan soal pertanggungjawaban hukum bagi kesalahan masa lampau bukanlah pelaku kesalahan itu sendiri ataupun rezim pelanggar, melainkan rezim suksesor.108 Reparasi transisional mengalihkan tindakan sipil yang konvensional dalam membedakan dan memilahkan pemberian tanggung jawab bagi pelanggaran hak-hak individual dari asumsi penggantian kerugiannya. Dalam prinsip kompensatoris tradisional, perilaku merugikan dan pertanggungjawaban hukumnya yang terkait diberikan kepada orang yang diidentifikasi sebagai pelaku, namun reparasi transisional pada umumnya diambil-alih oleh atau dibebankan kepada negara. Peralihan dalam prinsip reparatoris menguatkan transendensi dari prinsip konvensional tentang pertanggungjawaban individual, yang digantikan dengan pertanggungjawaban kolektif dalam masa transisi. Pemahaman tentang pertanggungjawaban individual/kolektif mucnul 106 Tentang teori keadilan kompensatoris, lihat Cass Sunstein, “The Limits of Compensatory Justice”, dalam John W. Chapman (ed.), Nomos XXXIII: Compensatory Justice, New York: New York University Press, 1991, 281. 107 Untuk pembahasan tentang problem terkait, lihat Judith Jarvis Thomson, Rights, Restitution and Risk: Essays in Moral Theory, Cambridge: Harvard University Press, 1986, 66-77. 108 Tentang pertanggungajwaban negara modern terhadap kesalahan atau pelanggarannya, lihat Peter H. Schuck, Suing Government: Citizen Remedies for Official Wrongs, New Haven: Yale University Press, 1983. 33 dalam pelbagai respon legal transisional yang dibahas dalam buku ini, yang memperumit soal pemahaman akan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan negara dan menyorotkan cahaya pada konteks-konteks keadilan yang dipermasalahkan dalam waktuwaktu seperti itu. Selanjutnya, pemahaman soal tindakan pemulihan (reparatory) yang memprasyaratkan asumsi negara tentang tanggung jawab merupakan jalan untuk mengkonstruksi identitas politik yang diteruskan. Transisi, tidak seperti peralihan administrasi masa biasa, bukan merupakan contoh-contoh tentang sekadar beralih dari kewajiban negara pada masa sebelumnya, karena rezim sebelumnya gagal melakukan kewajiban semacam itu. Inilah yang merupakan paradoks dari transisi reparatoris. Sementara di antara pergantian biasa dalam administrasi, asumsi soal utang semata mengekspresikan kontinuitas dalam identitas negara dan dalam kedaulatan hukum, ketika ada transisi di antara sistem politik, penentuan tentang pertanggungjawaban mengizinkan adanya konstruksi kontinuitas politik, atau diskontinuitas politik dan perubahan normatif. Keadilan reparatoris transisional tidak dijustifikasi terutama oleh kepentingan korektif konvensional, tetapi lebih dijustifikasi oleh nilai-nilai politis eksternal yang berkaitan dengan kebutuhan politik yang mendesak pada masa itu. Suatu prinsip normatif terkait muncul berkenaan dengan apa itu suatu perbedaan yang dapat dikompensasikan dalam kaitan dengan perlakuan negara di masa lalu. Dalam praktik transisional, hukum dalam fungsi reparatorisnya memajukan tujuan yang secara eksplisit politis. Justifikasi negara untuk memberikan reparasi ada banyak dan kompleks, berdasarkan tujuan korektif tradisional, sekaligus tujuan redistributif yang transformatif. Prinsip “penindasan politik” memandu keadilan reparatoris transisional, bekerja sebagai prinsip yang membatasi proyek-proyek reparatoris yang secara teoretis tidak terbatas, sekaligus memediasi tanggung jawab individu dan kolektif. Reparasi bahkan digunakan untuk menjustifikasi transisi, karena klaim demikian dikatakan timbul dari pelanggaran terhadap kesetaraan, menunjukkan perbedaan dari rezim terdahulu. Pemberian ganti rugi merupakan simbol utama diskontinuitas dari masa lalu, menunjukkan potensi transformatif dari rezim baru. Signifikansi pemberian ganti rugi melampaui klaim-klaim individual, dan mengkonstruksikan pergeseran masyarakat ke negara liberal. Sebagai tanda dan praktik kedaulatan hukum liberal, tindakan remedial memungkinkan komitmen baru terhadap kesetaran politik dan penolakan terhadap penindasan. Bahkan setelah jangka waktu yang panjang, praktik-praktik ini masih dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang simbolis, yang dapat menumbuhkan norma-norma hak individual yang meliberalkan. Bahkan, bila belum ada transisi politik, reparasi merupakan simbol modern liberalisasi, yang menggambarkan pendekatan yang dinamis terhadap hak dalam era global ini. 34 Bab 5 Keadilan Administratif Bab ini akan melihat pada situasi-situasi ketika hukum menjadi pendorong perubahan revolusioner. Dalam transisi politik sebagai hasil negosiasi, transformasi sering kali bergantung pada kekuatan hukum. Hukum publik yang dipolitisasi dapat menimbulkan perubahan radikal bila ia mendistribusikan kekuasaan secara eksplisit berdasarkan ideologi yang baru. Tindakan administratif yang dipolitisasi dalam skala besar sering kali dilakukan dalam masa-masa perubahan politik di seluruh dunia: setelah Perang Saudara Amerika Serikat, dalam pergeseran dari perbudakan ke kebebasan; di Eropa pasca-perang, dalam pergeseran dari fasisme ke demokrasi; di Eropa pasca-komunis, dari totalitarianisme ke ekonomi pasar yang lebih bebas; dan di Amerika Latin pasca-rezim militer, dalam pergeseran ke pemerintahan sipil. Pelaksanaan hukum administratif yang dipolitisasi dikatakan selalu diarahkan ke tujuan yang mulia, yaitu untuk melindungi transisi; namun, pernggunaan hukum demikian, yang berdasar pada keputusan yang kategoris, menyerupai keadilan politis di rezimrezim totaliter. Tindakan-tindakan demikian menimbulkan pertanyaan: apa kaitan cara-cara non-liberal dengan tujuan liberal? Bila ideologi non-liberal telah merasuki masyarakat, bagaimana cara masyarakat itu bisa diarahkan ke sistem politik yang lebih liberal? Apa potensi revolusi melalui hukum? Sejauh mana masyarakat transisional bergantung pada kebiasaan politik masa lalu sebagai dasar transformasi? Apa parameter normatifnya bila ada? Apa justifikasi untuk politisaasi tersebut? Bagaimana kepentingan rezim penerus bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjamin hak-hak individual? Dilema yang timbul ini berkaitan dengan cara dan tujuan. Apakah keadilan administratif transisional merupakan hal buruk yang diperlukan untuk mengarah ke transformasi kemasyarakatan? Dilema utama dalam hal ini terlihat dalam diskusi antara Arthur Koestler dan Maurice Merleau-Ponty tentang “pembersihan” (purge) era Stalin. Dalam argumen mereka, Koestler dan Merleau-Ponty menggunakan tokoh “komisaris” dan “yogi” untuk menggambarkan kedua kubu yang bertentangan itu: sang komisaris membela pembersihan politik karena ia percaya pada revolusi dan bahwa “tujuan menghalalkan segala cara”, dan sang yogi menentang pembersihan karena ia percaya bahwa perubahan revolusioner tidak mungkin terjadi, sehingga ia menyimpulkan “karena sasaran itu bersifat tidak dapat diramalkan ... cara-lah yang menjadi penting”.1 Pertanyaannya adalah: apa kegunaan dan justifikasi cara dan tindakan yang jelasjelas bersifat politis yang diambil dalam masa perubahan politik radikal? Inilah subjek yang akan dibahas dalam bab ini. Setelah berakhirnya pemerintahan represif, timbul pertanyaan penting: apa kaitan suatu pemerintahan yang jahat dengan warganya? Revolusi memiliki arti perubahan di tingkat kepemimpinan; namun, untuk mengadakan perubahan politik yang substansial, diperlukan lebih dari sekadar pergantian pemimpin di tingkat teratas. Dan, sering kali masyarakat transisional menggunakan tindakan administratif secara luas untuk mendistribusikan ulang kekuasaan antara warga negara. Bagaimana masyarakat yang sedang mengalami transformasi 1 Arthur Koestler, The Yogi and the Commissar, and Other Essays, New York: Macmillan, 1945; lihat Maurice Merleau-Ponty, Humanism and Terror: An Essay on the Communist Problem, Boston: Beacon Press, 1969. 1 berpikir tentang penggunaan cara-cara yang berdasarkan pada kelas politik? Intuisi kita adalah mengkonseptualkan tindakan-tindakan tersebut dengan cara yang antinomik: sebagai hukuman yang retrospektif, atau kondisi tatanan politik yang prospektif. Tindakan administratif transisional tampak paradoksal, dan tidak sesuai dengan intuisi yang berdasarkan pada hukum di masa biasa. Dalam beberapa hal, tindakan tersebut memandang ke depan, untuk mengadakan transformasi politik. Namun, di sisi lain, tindakan administratif transisional memandang ke belakang, seperti sanksi punitif. Dalam karakternya yang memandang ke belakang ini, respon-respon demikian menyerupai sanksi pidana; sementara dalam memandang ke depan, tindakan-tindakan ini merupakan usaha berskala besar untuk menyusun kembali komunitas, institusi dan proses politik, dan dalam hal ini keadilan administratif menyerupai langkah-langkah konstitusional. Berkaitan dengan pertentangan antara sifatnya yang memandang ke belakang sekaligus ke depan adalah subjek peraturan ini, yang mencakup individu maupun kolektif. Peradilan pidana biasanya berusaha menentukan tanggung jawab individual terhadap kesalahannya, namun tirani negara birokratik modern menyebarluaskan tanggung jawab dalam seluruh pemerintahan. Sehingga, penggunaan hukum pidana biasa tidak tepat, terutama bila mereka yang terlibat dalam represi di masa lalu tidak hanya tidak dihukum, namun masih tetap memegang kekuasaan dalam rezim yang baru. Sementara sanksi pidana biasanya ditimbulkan dari kesalahan individual, sanksi perdata yang bersifat administratif didasarkan pada syaratsyarat untuk penyingkiran, terutama loyalitas politik, yang secara sistematis mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu secara keseluruhan dari pemerintahan yang baru. Syarat kategoris yang muncul terus menerus dalam respon transisional ini memiliki bentuk yang tegas: suatu kebijakan penyingkiran, yang mengingatkan kita pada teori politik Thomas Hobbes, yang kemudian muncul kembali dalam tulisan Carl Schmitt, yaitu bahwa “tindakan dan motif politik dapat direduksi menjadi ‘kawan’ dan ‘lawan’”.2 Suatu hukum perdata yang terpolitisasi dapat menciptakan rezim politik yang baru, dengan menunjukkan pergeseran pemegang kekuasaan konstitutif dan kedaulatan. Respon kolektif yang bersifat ideologis tidak bisa dilepaskan dari politik dalam transformasi. Dilema keadilan administratif tergambar dalam pengalaman dari masa kuno, Amerika Serikat pasca-Perang Saudara, Eropa pasca-Perang, Amerika Latin pasca-rezim militer dan dekomunisasi bekas blok Soviet. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian praktis yang merupakan gabungan hukum dan politik diciptakan dalam masa-masa pergolakan. Dengan penggabungan tersebut, proses-proses dan justifikasi bersama menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan mereka, namun terkait dengan keperluan transformatif. Pembahasan tentang contoh-contoh historis di bawah ini menggambarkan peran praktik-praktik tersebut dalam transformasi radikal. Sodom dan Gomora: “Pembersihan” Dua Kota yang Jahat 2 Carl Schmitt, The Concept of the Political, terjemahan George Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 1996, 26. 2 Pertanyaan inti yang dicoba dijawab dalam bab ini adalah kaitan politik individu dengan politik kolektif dan bagaimana kaitan ini dipikirkan kembali dan dibangun kembali dalam transformasi politik radikal. Sejak masa kuno pun, pertanyaan ini dianggap sebagai inti kemungkinan perubahan politik. Ini tampak dalam kisah biblikal tentang dialog terkenal tentang rencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, dua kota yang dikatakan “bejat”.3 Kedua kota itu memperlakukan tamu-tamunya dengan buruk – mulai dari ketidakramahan hingga usaha pemerkosaan. Setelah kekejaman ini dilakukan, pertanyaannya adalah: respon apa yang tepat, dan apakah kedua kota itu harus dihancurkan karena dosa-dosa mereka? Dilemanya adalah apabila kota-kota itu harus dihancurkan, itu berarti bahwa orang-orang benar akan ikut musnah bersama orang-orang berdosa. Pertanyaan utamanya adalah: apa kaitan warga dengan identitas politik dari kota itu, dan sejauh mana keberadaan warga negara yang “baik” mempengaruhi identitas suatu kota? Kisah biblikal ini menunjukkan kaitan yang subtil antara identitas politik kota dengan identitas warganya, antara kolektif dan individual. Kota-kota tersebut tidak bisa diselamatkan hanya karena ada satu orang benar. Dalam tawar menawar, jumlah orang benar yang diperlukan untuk menyelamatkan kota dimulai dari lima puluh, “Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni tempat itu karena mereka”, dan turun hingga sepuluh, “Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu”.4 Terdapat titik balik dalam kaitan antara identitas individual dan kota yang menjadi batas identitas kolektif politik. Lebih lanjut lagi, apakah keberadaan beberapa orang benar sudah cukup (untuk tidak memusnahkan kota-kota itu)? Menyelamatkan kota-kota itu menimbulkan pertanyaan tidak saja tentang jumlah orang benar yang cukup, namun juga tentang apa yang menyusun suatu komunitas politik. Kisah tersebut menyatakan bahwa orang-orang benar tersebut harus ditemukan “dalam kota Sodom”, yang memiliki arti bahwa mereka haruslah ikut berpartisipasi dalam lingkup publik.5 Dalam sebuah kota yang layak diselamatkan, paling tidak harus ada sepuluh warga yang merupakan komunitas yang berpartisipasi dalam politik. Bahkan, pemahaman tentang politik yang “bersih” sebagai syarat partisipasi dalam lingkup publik tampak dalam teori politik Aristotelian di kemudian hari. Pesan tentang apa yang menyusun masyarakat sebagai hal yang normatif dipertegas dalam bagian lain dalam kisah biblikal tersebut. Lebih luas dari pertanyaan ini adalah tentang apa kaitan yang tepat antara individu dan kolektif, yang ditentukan dalam redefinisi afiliasi politik berdasarkan batas keanggotaan dan partisipasi. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kota-kota yang bejat ini dengan sendirinya berkaitan dengan kebejatan seluruh warga kotanya, karena mereka telah melanggar prinsipprinsip mendasar keadilan sosial yang mencakup perlakuan buruk terhadap tamu-tamu. Sejak masa kuno, warga asing yang berada di luar komunitas politiknya secara normatif tetap dilindungi tanpa memperhatikan batas negara. Pertanyaan tentang respon apa yang diperlukan – terhadap penganiayaan orang-orang asing, di luar perlindungan hukum komunitas tersebut – tetap relevan hingga masa modern ini. 3 W. Gunther (ed.), “Genesis”, dalam The Torah: A Modern Commentary, New York: Union of Hebrew Congregations, 1981, 18: 16-19: 38. 4 Ibid., 18: 23-32. 5 Lihat Nehama Leibowitz, Studies in the Book of Genesis, in the Context of Ancient and Modern Jewish Bible Commentary, terjemahan Aryeh Newman, Yerusalem: World Zionist Organization, Department for Torah Education and Culture in the Diaspora, 1976, 185-86. 3 Dalam kisah biblikal ini, legitimasi kedua kota ini masih perlu ditentukan terlebih dahulu. Kedua kota ini pada akhirnya dimusnahkan, namun tidak secara sewenang-wenang. “Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat ...”6 Bahkan, Yang Maha Mengetahui pun masih merasa perlu melakukan penyelidikan. Kebenaran politik, atau loyalitas, adalah hal yang diselidiki melalui proses publik, sesuai dengan kondisi dan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti dalam ilustrasi klasik ini, proses “evaluasi” inilah yang merupakan bagian keadilan administratif, yang berpuncak pada ritual-ritual politik lustrasi, yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam bab ini. Meskipun intuisi liberal menekankan signifikansi tindakan individual, syarat perubahan menuju masyarakat sipil seperti ditunjukkan dalam kisah klasik tersebut tidaklah semata-mata terkait dengan individu, namun mencakup pula hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Pemusnahan kedua kota tersebut menunjukkan bahwa identitas politik suatu kelompok politis berdasarkan pada batasan minimal kelompok politik berdasarkan jumlahnya. Terdapat juga kaitan antara masa lalu kota-kota tersebut dengan masa depannya: sejarah kejahatan di kota-kota itu memiliki dampak penting, karena mengakibatkan kehancurannya di masa berikutnya. Keputusan ini bersifat radikal dan absolut: karena kejahatannya di masa lalu, kota-kota tersebut kehilangan masa depannya. Transformasi politik mutlak diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan politik, dan meskipun terdapat intuisi liberal yang sering dikonstruksikan untuk memberikan nilai tambah pada peran individu, usaha transformasi politik memiliki persyaratan, yaitu keberadaan badan partisipatoris. Pemusnahan kedua kota ini merupakan contoh awal peran sanksi kolektif dalam transisi politik. Pada dasarnya pemusnahan ini menggambarkan keterbatasan dan batas-batas kemungkinan perubahan. Merekonstruksi Amerika Mungkin eksperimen terbesar dalam rekonstruksi identitas politik melalui hukum publik terjadi pada abad ke-19. Kasus ini memiliki relevansinya karena ia menggambarkan peran konflik politik yang berkelanjutan dengan lingkup perubahan politik dan batasan-batasan terhadap tindakan-tindakan politis yang dijalankan dalam sistem demokrasi konstitusional. Setelah Perang Saudara di Amerika, masa yang dikenal sebagai Rekonstruksi adalah masa pergulatan nasional tentang transformasi negara Serikat tersebut. Dalam masa ini terdapat dilema tentang bagaimana merespon konflik berdarah yang menimbulkan banyak korban, suatu lembaran hitam dalam sejarah negara tersebut, ketika perbedaan politis diselesaikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Konstitusi. Ilegalitas inilah – sifat Perang Saudara yang ekstrakonstitusional – yang merupakan titik tolak rekonstruksi. Jika Perang Saudara dan pemisahan Konfederasi dianggap terjadi di luar hukum, timbul pertanyaan tentang bagaimana menunjukan ketidaktaatan Selatan ini. Bagaimana Serikat dikhianati? Apakah Serikat dikhianati oleh negara-negara bagian “pemberontak”, sebagai negara bagian, atau oleh warganya, sebagai warga “pemberontak”? Dan, bila pelanggaran dilakukan oleh individu maupun negara bagian, apa arti rekonstruksi? Rekonstruksi lebih dari sekadar restorasi – ia memiliki arti perubahan politik yang lebih luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi kaitan antara masa lalu Serikat dengan masa depannya, 6 Plaut (ed.), “Genesis”, 18:20-21. 4 negara-negara bagian yang memberontak dan warganya. Rekonstruksi menyoroti kemungkinan restrukturisasi individu, warga negara dan negara, dalam gejolak politik yang radikal. Sejauh mana negara-negara bagian yang memberontak dapat menjadi anggota sepenuhnya dan setara dalam Serikat yang baru? Apakah loyalitas politik di masa lalu berkaitan dengan representasi politik di masa depan dalam Serikat? Apakah negara-negara bagian yang memberontak dan warganya dapat dianggap sebagai pengkhianat dan dipidana? Dan, meskipun pada masa perang mereka dijatuhi status penjahat perang, apakah anggota Konfederasi dan pendukungnya akan direstorasi? Tindakan pidana sejauh mungkin dihindari, selain pengadilan pemimpin Konfederasi, Jefferson Davis dan Kapten Henry Wirz, kepala kamp tahanan Andersonville. Namun, apakah suatu Serikat yang demokratis dapat dibentuk dari anggota-anggota Konfederasi yang belum direkonstruksi? Bahkan bila dapat dibayangkan suatu tatanan baru yang mencakup para mantan pendukung Konfederasi, paling tidak pada jajaran atas akan ditarik suatu garis yang mensyaratkan pergantian kepemimpinan dan representasi negara-negara bagian Selatan. Amerika pasca-Perang Saudara menunjukkan masalah besar tentang bagaimana merespon ketidaktaatan dan bagaimana menciptakan kepercayaan terhadap pemerintahan nasional yang baru. Dasar kebijakan Rekonstruksi adalah pemisahan diri dan ilegalitasnya. Sebagai parameter batasan politis dan juridis, disahkanlah amendemen konstitusional baru yang menyatakan ilegalitas pemisahan diri tersebut. Ilegalitas pemisahan diri tersebut memberikan implikasi diskontinuitas legal antara rezim, antara Konfederasi dan Serikat. Ilegalitas ini dinyatakan secara eksplisit dalam suatu provisi konstitusional yang menghilangkan tanggung jawab untuk hutang-hutang yang ditimbulkan oleh negara-negara bagian pemberontak selama perang.7 Bahkan meskipun tidak diperdebatkan lagi bahwa Konfederasi telah dihancurkan sebagai satu entitas legal, negara-negara bagian yang memisahkan diri tersebut masih ada sebagai entitas politik dan juridis, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengembalikan hak-hak mereka dan bagaimana memasukkan kembali mereka ke dalam Serikat. Dalam Serikat yang baru ini, respom publik luas melakukan pelucutan politik (political disability) bagi negara-negara bagian Konfederasi dan warganya, dan menentukan kembali batas politik Serikat melalui hukum konstitusional.8 Selama Rekonstruksi, selalu terdapat pertanyaan tentang bagaimana memperlakukan negara-negara bagian pemberontak dan warganya, serta kebijakan transisional manakah yang memandu hubungan ini. Rekonstruksi Amerika memiliki arti suatu perubahan dalam kaitan antara individu dan kolektif, warga negara dan negara. Bahkan, keruntuhan rezim perbudakan dan konsolidasi republik bergantung pada rekonstruksi kaitan ini. Sepanjang sejarah, pengucapan sumpah setia dipergunakan untuk membantu mengkonsolidasikan suatu kemunitas politik yang rapuh dan terbelah. Semakin retak kelompok politik tersebut, semakin besar tekanan untuk menyatukannya. Suatu bentuk kebijakan Rekonstruksi yang relatif lunak disarankan pada masa Presiden Abraham Lincoln, yaitu dengan menyuruh para mantan pendukung Konfederasi mengucapkan sumpah setia kepada Serikat. Rencana ini bisa 7 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 4 (menyatakan bahwa “baik Amerika Serikat maupun negara lainnya tidak akan menanggung atau membayar hutang atau kewajiban yang ditimbulkan dari bantuannya terhadap insureksi atau pemberontakan melawan Amerika Serikat ... semua hutang, kewajiban dan klaim demikian akan dianggap ilegal dan tidak sah”). 8 Lihat misalnya, Texas v. White, 74 US 700 (1868). 5 diterapkan secara universal, sebagai pernyataan persetujuan secara publik kepada pemerintah yang baru, untuk menunjukkan kesetiannya.9 Penggunaan sumpah demikian telah dimulai sejak transisi lebih awal dari Inggris, di mana Konstitusi Amerika mewajibkan sumpah menurut Konstitusi bagi semua orang yang hendak menduduki jabatan publik, untuk menunjukkan kesetiaan, bukan kepada raja yang berada entah di mana, namun kepada Konstitusi. Bila sepuluh persen dari negara-negara Konfederasi sepakat untuk mengucapkan sumpah setia kepada Amerika Serikat, pemerintahan negara bagian yang baru akan diakui, dan pengampunan serta restitusi hak milik akan diberikan. Sumpah kesetiaan model Lincoln ini ditujukkan untuk memungkinkan transformasi dari pemberontak, ke negara-negara bagian yang dikembalikan hal legalnya, namun rencana ini tidak bertahan lama, dan digantikan oleh kebijakan yang lebih keras. Kebijakan Rekonstruksi yang merujuk pada syarat-syarat konstitusional dalam Amendemen XIV pada umumnya bersifat prospektif; syarat-syarat yang diberikan kepada negara-negara Selatan dan warganya untuk kembali menjadi anggota Serikat menunjukkan komitmen umum terhadap prinsip utama kesetaraan di muka hukum. Rehabilitasi negaranegara bagian disyaratkan pada ketaatan pada Amendemen XIV dan XV, dan disepakati oleh badan-badan perwakilan negara bagian sebelum dinyatakan sah untuk memiliki perwakilan dalam kongres negara federal (Serikat).10 Demikian pula, syarat-syarat konstitusional ini dapat mendiskualifikasi siapa saja, yang sebelumnya melanggar sumpahnya untuk menjunjung Konstitusi dengan melakukan pemberontakan, dari jabatan publik. Sejarah legislatif ini menunjukkan dengan jelas bahwa pelucutan-diri secara konstitusional ini ditujukkan untuk menyingkirkan mantan pemimpin Konfederasi dari jabatan publik. Tidak seorang pun dapat menjadi Senator atau Wakil dalam Kongres, atau Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, atau memegang jabatan apa pun, sipil atau militer, dalam negara Amerika Serikat, atau dalam negara-negara bagiannya yang mana pun, yang sebelumnya telah mengambil sumpah, sebagai anggota Kongres, atau sebagai pejabat Amerika Serikat, atau sebagai anggota badan legislatif negara-negara bagiannya yang mana pun, untuk menjunjung Konstitusi Amerika Serikat, [namun] telah melakukan insureksi atau pemberontakan terhadap [Konstitusi] tersebut, atau memberikan bantuan kepada musuh-musuh [Konstitusi].11 Pelucutan-diri secara konstitusional ini diberi kekuatan dengan pengesahan sumpah “berlapis baja” (ironclad oath), yang mewajibkan seseorang untuk bersumpah bahwa sejak sebelumnya ia telah menjunjung Konstitusi sebelum ia dapat memegang jabatan publik di masa depan. Dengan rehabilitasi yang disyaratkan pada sumpah tersebut, identitas politik negara didefinisikan pada utamanya sebagai respon terhadap rezim sebelumnya. Sementara sumpah kesetiaan Lincoln merupakan ekspresi penegasan kesetiaan di masa mendatang yang melihat ke depan, sumpah ironclad ini kebalikannya, sebagai ungkapan penolakan memandang ke 9 Lihat Jonathan Truman Dorris, Pardon and Amnesty under Lincoln and Johnson: The Restoration of the Confederates to Their Rights and Privileges, 1861-1898, Westport, Conn: Greenwood Press [1953] 1977. 10 Lihat White v. Hart, 80 US 646 (1871) (menjelaskan bagaimana Akta Rekonstruksi mewajibkan negara-negara bagian yang memberontak untuk menaati syarat-syarat yang ditentukan Kongres untuk dapat dikembalikan ke statusnya sebelum melakukan pemberontakan). 11 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 3 (“Namun Kongres bisa, dengan melakukan pemungutan suara yang disepakati dua pertiga dari masing-masing kamar, mencabut pelucutan tersebut”). Bagian ini mulai diberlakukan pada bulan Juli 1868. 6 belakang. Seperti sumpah kanonik di masa lampau,12 sumpah ironclad berfungsi sebagai ujian kebenaran politik, yang digunakan untuk membersihkan seseorang dari tuduhan atau kecurigaan, dengan melakukan sumpah tersebut. Meskipun sumpah ironclad ini adalah suatu tindakan yang keras, bahasa konstitusional dalam amendemen Rekonstruksi mencerminkan ambivalensi yang mendalam tentang penerapannya. Tidak seperti provisi konstitusional lainnya yang dapat diterapkan dengan sendirinya, pelucutan politik mensyaratkan adanya konsensus politik yang berjalan. Terlebih lagi, dalam amendemen konstitusional ini, Kongres secara eksplisit diberi kekuasaan untuk mengesampingkan ketentuan soal pelucutan politik itu,13 yang menunjukkan bahwa amendemen Rekonstruksi ini tidak memiliki status konstitusional dan dianggap sebagai tindakan ad hoc –diperlukan hanya untuk kepentingan politis. Pelucutan politik Rekonstruksi pada akhirnya tidak berlangsung lama. Selama beberapa tahun, Kongres secara teratur menjalankan kekuasaannya: membuat perundangundangan amnesti dan secara teratur mencabut pelucutan politik.14 Dalam Kongres ke-42, pelucutan ini ditetapkan hanya berlaku bagi jabatan tinggi dalam politik. Pada tahun 1872, atas dorongan Presiden Ullysess Grant, Kongres membebaskan semua orang dari pelucutan konstitusional, kecuali pejabat tinggi politik, seperti wakil dalam Kongres dan hakim federal. Akhirnya, pada tahun 1878, enam tahun setelah dilaksanakannya, pelucutan politik yang terbatas ini bahkan dicabut, dan hanya menyisakan provisi konstitusional untuk mencabut hak dipilih menjadi wakil. Namun, pelucutan-diri secara konstitusional tetap dipergunakan sebagai alat peringatan, sebagai cara diskualifikasi de facto dari jabatan publik atas dasar politik. Pelucutan politik era Rekonstruksi masih tetap ada dalam Konstitusi Amerika, di mana mereka merupakan ekspresi politik sejarah yang membentuk identitas Amerika Serikat. Kebijakan rekonstruksi bersifat kontroversial karena ia secara mendasar menata ulang hubungan negara bagian federal, yang kemudian akan mendapatkan tantangan di pengadilan. Pertanyaan konstitusionalnya adalah prinsip apa yang mengatur hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian, pemerintah dan warga. Dalam sistem federal, pemerintah mana yang memiliki otoritas untuk menentukan status dan hak warga negara, dan siapa yang harus ditaati oleh warga negara? Terlebih lagi, ke mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarahkan penciptaan kembali identitas politik negara? Dalam tinjauannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada umumnya merujuk pada cabang-cabang politik dan agenda Rekonstruksi. Dalam kasus Mississippi v. Johnson, Georgia v. Stanton dan Texas v. White, kasus-kasus di mana negara-negara bagian yang memisahkan diri menentang batasan-batasan baru dari pemerintah, Mahkamah Agung menegaskan kebijakan Rekonstruksi.15 Jaminan konstitusional terhadap bentuk pemerintahan “republikan” dianggap sebagai kewajiban politik yang menyusun dasar perundang-undangan Rekonstruksi. Dengan menjunjung kebijakan transformatif dalam perimbangan kekuasaan federal-negara 12 Lihat Oxford English Dictionary, edisi kedua, entri “purgation: pembersihan kanonik (seperti dalam hukum kanonik), penegasan melalui sumpah tentang ketidakbersalahan seseorang oleh penuduh dalam pengadilan spiritual, diperkuat oleh sumpah beberapa rekannya”. 13 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV. 14 Seperti dijelaskan dalam provisi ini, diskualifikasi dibatalkan oleh Kongres pada tahun 1886. Lihat House Committee on the Judiciary, Removal of Disabilities Imposed by the Fourteenth Article of the Constitution, 55th Cong., 2nd sess., 1898, H. Rept. 1407. 15 Lihat Mississippi v. Johnson, 71 US (4 wall.) 475 (1867) (menegaskan peran cabang eksekutif dalam Akta Rekonstruksi); Georgia v. Stanton, 73 US (6 Wall.) 50 (1868); Texas v. White 74 US 700 (1868). 7 bagian, Mahkamah Agung menegaskan kembali peran cabang-cabang politik dengan mengizinkan Kongres untuk mengontrol akses ke tinjauan judisial pada isu-isu Rekonstruksi dengan menggunakan kekuasaannya untuk mencabut hukuman berdasarkan konstitusi.16 Meskipun pada umumnya Mahkamah Agung mengalah kepada Kongres, ia menegaskan perlunya akses pada pengadilan di masa damai dan due process.17 Dalam kasus-kasus sumpah kesetiaan, Ex Parte Garland dan Cummings v. Missouri, yang diputuskan pada tahun 1866, Mahkamah Agung mempertimbangkan dan mencabut konstitusionalitas pelucutan politik bagi para pendukung Konfederasi. Ex Parte Garland menyangkut konstitusionalitas sumpah ironclad, yang ditantang oleh seorang pengacara yang tidak bisa mengambil sumpah demikian, karena ia pernah menjabat di Pengadilan Arkansas, suatu negara Konfederasi. Dampak sumpah tersebut adalah bahwa ia tidak bisa lagi berpraktik, karena statusnya di masa lalu.18 Kasus lainnya, Cummungs v. Missouri, merupakan tantangan terhadap sumpah serupa dalam konstitusi negara bagian. Sebagai syarat untuk dapat memilih di negara bagian tersebut, selain memegang jabatan publik, mengajar dan bekerja dalam profesi lain, seperti menjadi pendeta, Konstitusi Missouri mewajibkan para calon untuk menyatakan apakah mereka pernah “mengangkat senjata melawan Amerika Serikat” atau “dengan tindakan atau kata-kata … menyatakan kesetiaan terhadap musuh-musuh Amerika Serikat”.19 Dalam kasus Garland dan Cummings, Mahkamah Agung menolak sumpah Rekonstruksi, dan menyatakan bahwa meskipun secara garis besar hal tersebut serupa dengan sanksi perdata, mereka merupakan bentuk hukuman yang tidak diizinkan. Pertanyaan yang relevan tentang apakah sumpah kesetiaan dapat dianggap sebagai kualifikasi valid untuk memegang jabatan publik, menurut Mahkamah Agung, bergantung pada kaitan antara tindakan yang relevan dan jabatan yang dimaksudkan, yaitu kekuatan hubungan antara cara-cara legislatif dan tujuan yang hendak dicapai. Mahkamah Agung menyatakan bahwa luasnya jangkauan sumpah ini membelokkan tujuan semula untuk menjamin ketaatan pada Serikat. Penerapan persyaratan politis ini dianggap sebagai kebijakan punitif. Meskipun sumpah ini memiliki bentuk perdata, pencabutan hak ini dianggap sebagai bentuk hukuman. Pelucutan secara luas tanpa memandang secara spesifik merupakan hambatan inkonstitusional terhadap kebebasan berasosiasi. Kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya juga dipermasalahkan, demikian pula apakah ada kaitan langsung antara diskualifikasi politik dan jabatan yang dipermasalahkan. Mahkamah Agung menolak tujuan Rekonstruksi dari pemerintah dan menyatakan bahwa secara konstitusional, hal demikian tidak bisa dirasionalisasikan dalam transformasi. Pelucutan pasca-Perang Saudara ini nyaris tidak bersesuaian dengan intuisi kita tentang penghukuman pada masa biasa: bahkan interpretasi konstitusional terhadap tindakan era Rekonstruksi ini dipandu oleh preseden transisional lainnya dalam masa-masa perubahan politik radikal dalam sejarah Anglo-Amerika. Undang-undang era Rekonstruksi serupa dengan apa yang dilarang dalam klausul “bill of attainder” dalam Konstitusi. Seperti juga bill of attainder, sumpah era Rekonstruksi dianggap sebagai penerapan hukuman tanpa proses judisial yang lazim. Ketiadaan proses judisial yang biasanya dikaitkan dengan pemberian hukuman, seperti perlindungan terhadap retroaktivitas, menjadikan sumpah tersebut inkonstitusional. Sepanjang sejarah Anglo-Amerika, tindakan serupa pernah diberlakukan, 16 Lihat Ex Parte McCardle, 74 US (7 Wall.) 504 (1869). Lihat Ex Parte Milligan, 71 US (4 Wall.) 2 (1866). 18 Lihat Ex Parte Garland, 71 US (4 Wall.) 333 (1866). 19 Lihat Cummings v. Missouri, 71 US (4 Wall.) 277, 279 (1866). 17 8 pertama kali oleh Parlemen Inggris dalam masa-masa pelanggaran oleh monarki, dan kedua, oleh negara-negara bagian setelah Revolusi Amerika. Yang mencirikan tindakan ini adalah bahwa mereka diterapkan oleh badan legislatif, dan mengambil dasar politis. Sepanjang sejarah, sanksi legislatif demikian secara tradisional digunakan untuk menindas oposisi politik. Seperti diamati Mahkamah Agung, undang-undang ini “paling sering digunakan di Inggris pada masa pemberontakan, atau ketidaktaatan terhadap kerajaan, atau gejolak politik dengan kekerasan; yaitu masa-masa di mana semua negara paling rentan ... untuk mengabaikan kewajiban mereka dan menginjak-injak hak dan kebebasan negara lainnya”.20 Sementara bill of attainder Inggris tidak memiliki justifikasi demikian, namun tetaplah dianggap sebagai bentuk hukuman yang seharusnya tidak diizinkan, meskipun memiliki alasan transformatif.21 Di masa kini, pemahaman konvensional tentang jurisprudensi era Rekonstruksi adalah bahwa ia menghalangi transformasi di masa tersebut.22 Masa tersebut dianggap sebagai titik terendah jurisprudensi Mahkamah Agung dan sering kali dihilangkan dari tinjauan hukum konstitusional. Namun, analisis di atas mendorong pemikiran ulang tentang doktrin masa tersebut. Dibandingkan dengan fenomena transisional serupa dalam masyarakat lainnya, era Rekonstruksi menunjukkan jurisprudensi terpolitisasi yang merupakan ciri masa gejolak politik. Jurisprudensi ini menunjukkan ketegangan dan inkoherensi antara hukum pidana dan perdata yang seharusnya terpisah, juga hukuman dan hukum administratif. Ia juga menguji batas hukum konstitusional, terutama sejauh mana politisasi diizinkan. Pertimbangan ulang tentang kasus Rekonstruksi dari perspektif transisional menantang pemahaman yang lazim tentang sifat dan peran hukum publik yang dipolitisasi. Bagi pengadilan era Rekonstruksi, referensi diambil dari masa-masa transformasi politik dalam sejarah negara itu. Presedenpreseden sejarah ini menunjukkan bahwa bahkan pada masa itu, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang diambil pada masa luar biasa dan transisional, karena Mahkamah Agung mengimbangkan pemikiran tersebut dengan ketaatan pada kedaulatan hukum konvensional. Jurisprudensi era Rekonstruksi dipandu oleh kompromi: seperti juga di negara-negara lain yang mengalami gejolak politik, jurisprudensi Amerika era Rekonstruksi mencerminkan keadilan konstitusional yang terbatas dan parsial. Dalam masa demikian, ajudikasi konstitusional mencerminkan kesetimbangan antara nilai-nilai kontinuitas dan diskontinuitas dan nilai-nilai kedaulatan hukum keamanan dan kesetaraan yang berpotensi dipertentangkan. Rekonseptualisasi politik konstitusional di masa itu memiliki implikasi pada perdebatan kontemporer tentang prinsip-prinsip yang relevan untuk memandu interpretasi konstitusional bagi amendemen-amendemen Rekonstruksi.23 Pengakuan kaitan amendemen Rekonstruksi dengan agenda politik luas pada masa itu memiliki implikasi untuk menafsirkan amendemen 20 Ibid., 323. Tentang perbedaan antara sanksi pidana dan perdata, lihat George P. Fletcher, “Punishment and Compensation”, Creighton Law Review 14 (1981): 691; Maria Foscarinis, “Toward a Constitutional Definition of Punishment”, Colombia Law Review 80 (1980): 1677. Lihat juga Elfbrandt v. Russel, 384 US 11 (1966); Kennedy v. Russel, 384 US 11 (19656); Kennedy v. Mendoza Martines, n372 US 144 (1963); Wiemann v. Updegraff, 344 US 183 (1952) menolak sumpah berkaitan afiliasi masa lalu dengan komunisme). 22 Untuk tinjauan kritis tentang pemahaman umum ini, lihat Stanley Kutler, Judicial Power and Reconstruction Politics, Chicago: University of Chicago Press, 1968. 23 Tentang perdebatan ini, bandingkan Raoul Berger, Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, Indianapolis: Liberty Fund, 1977 dengan Robert J. Kaczorowski, “Revolutionary Constitutionalism in the Era of the Civil War and Reconstruction”, New York University Law Review 61 (1986): 863. 21 9 tersebut berkaitan dengan program legislatif Rekonstruksi. Demikian pula halnya dengan kaitan pemahaman sejarah standar hak-hak sipil masa tersebut dengan kontroversi hak serupa di masa kini. Jurisprudensi era Rekonstruksi sebaiknya dipahami dari perspektif transisional, tujuan transformatif masa ini menjelaskan jurisprudensi pengambilan keputusan yang terpenting di masa tersebut dan menerangkan relevansinya dengan jurisprudensi konstitusional. Pembebasan Melalui Hukum “Saya tidak mengenal cara untuk mengajukan tuduhan kepada suatu bangsa.” (Edmund Burke, Pidato Perdamaian dengan Amerika) 22 Maret 1775 Dalam sejarah, proyek besar transformasi politik berikutnya adalah denazifikasi, yang diusahakan pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika Sekutu menegaskan bahwa para pendukung Nazisme harus diturunkan dari jabatan-jabatan berpengaruh di Jerman. Di satu sisi kebijakan pengadilan pasca-perang dirasionalkan sebagai tindakan retributif untuk membalas pelanggaran yang dilakukan Nazi, di Postdam. Namun, di sisi lain, rencana denazifikasi dijustifikasi untuk tujuan ke depan, yaitu demokratisasi. Denazifikasi dianggap perlu, untuk menjamin bahwa mereka yang memiliki kecenderungan fasis tidak lagi memegang kekuasaan. Namun bagaimana cara menjangkau semua orang demikian? Meskipun denazifikasi pascaperang bermula dengan pemikiran untuk melarang pejabat tinggi Nazi, SS, Gestapo, dan SD dari jabatan tertinggi dalam rezim baru, seiring perjalanan waktu, kebijakan ini diterapkan secara nyaris universal. Meskipun bertujuan untuk demokrasi yang memandang ke depan, secara mendasar skema ini juga memandang ke belakang. Dengan menggunakan konsep “kejahatan yang meraja-lela” pada masa Nazi, pengadilan Nuremberg memberikan pendekatan baru untuk menjawab pertanyaan tentang kaitan tanggung jawab individual dan kolektif dalam penindasan masa perang. “Buah pikiran Bernay” menggunakan pengadilan individual untuk memidana organisasi-organisasi Nazi, dan menuntut organisasi tersebut memerintahkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan masalah praktis bagaimana menjangkau semua orang yang terlibat. Setelah organisasi-organisasi tertentu menjadi “terpidana” oleh Tribunal Militer Internasional, dalam pengadilan lanjutannya, keputusan tentang organisasi menjadi dasar untuk keputusan tentang individu.24 Pengadilan individual tidaklah diperlukan; pembuktian keanggotaan dalam organisasi kriminal dianggap sudah cukup. Ide ini menimbulkan kontroversi karena pendekatannya yang cair terhadap tanggung jawab individual; ia menentang intuisi tentang kedaulatan hukum, yang memandu pandangan tentang status, hak dan tanggung jawab individual. Setelah Nuremberg, pemikiran bahwa Nazisme adalah “kejahatan” dianggap benar secara hukum. Kebijakan penghukuman oleh Tribunal membantu membentuk proses denazifikasi: ciri hukum pada masa ini adalah kontinuitas cair dalam penetapan tanggung jawab individu dan organisasi, selain sebagai penengah antara batas sanksi pidana dan perdata. 24 Lihat Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and the War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986. 10 Pada saat diciptakannya setelah perang, kebijakan denazifikasi dalam pemerintahan militer Sekutu di Jerman secara eksplisit dikaitkan dengan kebijakan peradilan pidana pascaperang yang disusun di Nuremberg, dengan dasar tanggung jawab organisasional. Pada tahap pertama, denazifikasi dibatasi pada diskualifikasi mereka yang memegang jabatan tinggi dalam partai Nazi dan organisasi “kriminal” lainnya (menurut Nuremberg). Namun, ketika kekuasaan dikembalikan kepada Jerman, tahap denazifikasi berikutnya yang lebih ambisius dimulai. Seperti namanya, Akta Pembebasan Jerman dari Nazisme dan Militerisme (5 Maret 1946), ditujukan untuk membersihkan Jerman dari ideologi Nazi. Tirani Nazi akan disingkirkan dari “pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan budaya”. Untuk mencapai tujuan tersebut, fragebogen (kuesioner) digunakan untuk menanyakan kepada semua warga negara dewasa untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di masa perang. Cakupan Akta Pembebasan yang luas ini menjangkau “pelanggar utama”, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga “pengikut”, yakni para pendukung Nazisme di tingkat bawah.25 Dasar untuk memberikan sanksi menurut hukum adalah cukup dengan membuktikan keanggotaan. Dengan kerangka pemberian sanksinya yang luas berdasarkan berbagai tingkat tanggung jawab, Akta Pembebasan merupakan skema penghukuman, yang menunjukkan sisi punitif denazifikasi. Sanksi yang menimbulkan pengurangan hak-hak sipil ini – dari pemenjaraan hingga penghilangan kesempatan bekerja dalam sektor publik dan lainnya – tampak sebagai bentuk hukuman. Namun, meskipun denazifikasi memiliki dampak punitif, sanksi perdata di dalamnya tidak memiliki fokus individual; prosedurnya bukanlah pidana dan hanya didasarkan pada proses administratif. Di satu sisi, seperti dibicarakan dalam bab 2, peradilan pidana dalam transisi sering kali melibatkan proses yudisial yang tidak berpuncak pada pemberian hukuman sepenuhnya. Sementara di sisi lainnya, tindakan administratif transisional sering kali menimbulkan hal sebaliknya: sanksi punitif tanpa melalui proses yudisial yang lengkap. Hampir semua pengamat menyatakan bahwa kebijakan denazifikasi gagal. Hampir semua orang yang disorot dalam skema tersebut dikatakan sebagai “pengikut” – tingkat terendah dalam tanggung jawab politik. Mereka yang dihukum hanya mendapatkan sanksi denda; hanya sedikit yang dilarang menjabat, itu pun untuk jangka waktu yang pendek. Lama setelah denazifikasi, banyak anggota elite yang bekerja-sama dengan Nazi masih tetap memegang jabatan mereka; bahkan institusi peradilan pun masih tetap dikuasai oleh mantan anggota Nazi.26 Bertahun-tahun kemudian, pertanyaan tentang bagaimana menyikapi para pejabat era Nazi menjadi sangat kontroversial, sehingga tidak pernah mencapai konsensus; dalam undang-undang dasar yang baru, pertanyaan ini dialihkan kepada cabang politik di waktu yang lain. Anehnya, justifikasi yang digunakan untuk melakukan denazifikasi kembali digunakan untuk merasionalkan kebijakan pengembalian kedudukan para mantan Nazi. Keanggotaan dalam partai Nazi sedemikian besarnya, sehingga melanjutkan kebijakan denazifikasi akan berarti menurunkan banyak hakim yang ada. Pengalaman sebelumnya dalam pemerintahan, meskipun dalam rezim Nazi, dijadikan alasan untuk integrasi ke dalam sistem layanan publik. Bahkan sebenarnya, tidak lama setelah kebijakan denazifikasi disahkan, disahkan pula Akta Pengembalian Kedudukan, yang mengembalikan jabatan para pejabat mantan Nazi, dan dengan demikian menghentikan denazifikasi. 25 26 Lihat Act for Liberation from National Socialism and Militarism, Pasal 1 (Jerman, 1946). Lihat Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, Cambridge: Harvard University Press, 1991. 11 Dalam kritik standar terhadap kebijakan denazifikasi, kegagalan terletak pada kelemahan dalam pelaksanaannya karena konteks politik: jumlah yang sedemikian besar sehingga tribunal tidak dapat melakukan penyaringan, ketiadaan keinginan politis, terutama akibat Perang Dingin, dan kesukaran usaha untuk “pembersihan diri sendiri”. Terdapat pula kaitan antara denazifikasi dan kebijakan penghukuman, sehingga ketika proses pengadilan berakhir dengan pengampunan, denazifikasi menjadi sukar untuk dilanjutkan.27 Luasnya denazifikasi yang mencakup semua pejabat dalam sistem administrasi publik menjadikan pelaksanaannya amat sukar. Kritik standar denazifikasi ini timbul dari perspektif realis; denazifikasi gagal karena kondisi politiknya. Namun, kritik standar ini tidak menjelaskan apakah memang ada yang salah dengan kebijakan ini, karena ia mengaitkan relevansi masa lalu politik Jerman dengan konstruksi layanan publik rezim baru dan transformasi demokratik. Selanjutnya, perlu pula dipertanyakan keluasan cakupan kebijakan denazifikasi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan tingkat keterlibatan, selain juga posisi yang terpengaruh; jadi, misalnya, perlu dibedakan pembersihan secara besar-besaran seluruh sektor layanan publik dengan penyaringan elite-elite politik tingkat tinggi dan aparat keamanan. Pertanyaan normatif ini menuntut adanya justifikasi terhadap kebijakan keadilan administratif transisional. Justifikasi ini adalah “pembangunan demokrasi”. Menyingkirkan Nazi dari layanan publik dianggap perlu untuk merekonstruksi demokrasi Jerman. Mempertahankan sistem aparat administratif yang sudah ada dianggap akan melemahkan kemungkinan transisi menuju sistem yang lebih liberal. Namun, apa persisnya kaitan antara perilaku politik di masa lalu dalam pemerintahan represif, dan kemungkinan berpartisipasi dalam rezim liberal yang menggantikannya? Intuisi kita adalah bahwa sistem demokrasi liberal tidak akan bisa terbentuk di bawah kepemimpinan mantan pemimpin Nazi. Dalam sistem demokrasi yang mapan, perubahan politik di tingkat eselon tinggi pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum secara teratur. Namun, dalam masyarakat yang mengalami transisi sistem politik, metode representasi politik yang teratur ini sering kali belum siap. Terlebih lagi, tidak semua pejabat publik dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, pergantian rezim setelah negosiasi bergantung pada hukum untuk mendefinisikan batasan politik baru terhadap ranah publik. Dalam kondisi politik demikian, pergantian rezim melalui pencopotan mereka yang memegang kekuasaan secara umum didorong oleh hukum. Justifikasi lazim untuk pembersihan politik adalah untuk menyingkirkan rezim lama dan para pendukungnya dari partisipasi politik dalam demokrasi. Apa peran persyaratan politik dalam rezim yang menuju sistem liberal? Klaim utama dalam argumen demokrasi yang sering digunakan dalam transisi adalah anggapan bahwa mereka yang di masa lalu melakukan represi akan melakukannya lagi di masa depan, sehingga melemahkan konsolidasi demokrasi. Justifikasi demokrasi ini menjadi paling kuat bila posisi yang dipermasalahkan ini sama dengan yang dipegang di masa lalu, terutama bila memungkinkan timbulnya represi. Dengan demikian, meskipun keanggotaan partai saja mungkin tidak bisa menjustifikasi pencopotan dari jabatan tingkat rendah, tidaklah demikian dengan posisi tinggi atau pembuat kebijakan dalam rezim yang baru, atau posisi dalam aparat keamanan negara, yang memungkinkan pelanggaran hak. Semakin erat kaitan antara pelucutan politik dengan posisi yang terpengaruh, semakin relevan pula justifikasi demokrasi ini. Namun, dalam hal ini, denazifikasi tidak berkaitan dengan kebijakan transisional, karena tidak 27 Untuk tinjauan sejarah masa tersebut, lihat John Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Wesport: Greenwood Press, 1982, 1-38. 12 ada kaitan antara pelucutan politik secara luas dengan demokrasi. Sebaliknya, tanpa memperhatikan pertimbangan moral, kompetensi mereka yang telah berpengalaman dalam bidang politik, administrasi dan manajerial – dalam rezim lama – seharusnya lebih tinggi. Pada akhirnya, argumen demokrasi ini tampaknya salah arah dan inkoheren: karena kekuatan justifikasi demokrasi untuk pelucutan politik diletakkan pada asumsi bahwa demokrasi akan dibentuk dari orang-orangnya, bukan pada struktur, institusi dan prosedur. Pemikiran ini tidak sesuai dengan teori politik liberal. Denazifikasi pasca-perang, seperti pelucutan politik era Rekonstruksi, sebaiknya dipahami dalam konteks transisionalnya. Pertimbangan terhadap arahan kebijakan menggarisbawahi sifatnya yang transisional dan pergeseran kesetimbangan yang terjadi selama masa transisi. Kebijakan denazifikasi dimulai pada akhir perang, dan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Kebijakan ini menyurut setelah lima tahun, sampai tahun 1950; dan sejak tahun 1951 tahap transisional telah berakhir. Urutan ini menunjukkan proses penyusunan kembali sistema administrasi negara. Meskipun banyak kritik terhadap kebijakan denazifikasi berfokus pada kegagalannya untuk menyingkirkan para mantan Nazi secara permanen, namun kebijakan ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam hal ini adalah untuk memajukan transformasi. Dengan demikian, sifatnya yang parsial dan provisional hanyalah menunjukkan ciri dari dinamika politik masa tersebut.28 Meskipun tepat setelah perang berakhir, kaitan dengan rezim fasis berakibat fatal terhadap partisipasi politik. Setelah jangka waktu tertentu, kaitan politik demikian menjadi dapat diterima, dan bahkan diharapkan dalam rezim penerus. Pengalaman dalam pemerintahan, meskipun pemerintahan Nazi, menjadi dasar untuk integrasi dalam layanan publik.29 Partisipasi dalam rezim terdahulu menjadi hal yang normal setelah pergeseran administrasi biasa. Perlakuan terhadap rezim lama bergeser dari diskontinuitas menjadi kontinuitas. Pada awalnya, perundang-undangan denazifikasi didorong oleh tujuan utama untuk mengembalikan legitimasi. Dengan semakin mapannya rezim penerus, kebijakan publik memberi jalan bagi tujuan-tujuan lainnya. Bila dilihat secara berdiri sendiri, kebijakan denazifikasi secara umum dianggap sebagai kegagalan usaha transformasi. Namun, bila dilihat dari perspektif historis-komparatif, bersama-sama dengan tindakan lain yang diambil pada masa-masa gejolak politik radikal, pengalaman ini ternyata menunjukkan kesesuaian dengan norma-norma transisional. Pembersihan administratif terjadi pada masa tatanan politik yang rapuh dan tidak stabil; tindakan demikian bersifat sementara selama masa transformasi politik. Sejak awalnya, tindakan demikian bersifast pragmatik, ditujukkan sebagai peralihan, untuk masa rekonstruksi politik tertentu. Tindakan-tindakan ini adalah bagian dari keadilan transisional. Epuracion dan Zuivering: Politik Penyingkiran Sementara di Jerman selama masa pendudukan Sekutu terdapat rasa tanggung jawab kolektif secara luas, sebaliknya, di wilayah-wilayah lainnya di Eropa pasca-perang, terdapat musuh yang harus disingkirkan. Pembebasan dari Nazisme berjalan seiring dengan pembersihan secara besar-besaran para pendukung rezim sebelumnya. Dasar untuk pembersihan ini jelasjelas ideologis: keadilan masa pasca-pendudukan diciptakan berdasarkan pertentangan kami28 29 Lihat John Herz, “The Fiasco of Denazification in Germany”, Political Science Quarterly 18 (1948): 569. Lihat Müller, Hitler’s Justice. 13 mereka, kawan-lawan dan kolaboratos-pejuang; ia merupakan rekonstruksi melalui dekonstitusi. Setelah runtuhnya rezim-rezim pendudukan di Eropa pasca-perang, masyarakat merespon ranah publik yang amat terkompromi karena dukungannya terhadap kekuasaan fasis. Dalam transisi dari fasisme, penciptaan garis batasan kawan-lawan melampaui batasan rekonstruksi sistem administrasi, ke lingkup publik yang lebih luas yang mencakup semua elemen masyarakat. Praktik pembersihan Eropa pasca-perang menunjukkan bagaimana keadilan administratif mencakup pengabaian terhadap proses-proses pidana yang lazim dan menggunakan proses-proses yang lebih luas dan informal, mengabaikan peradilan dan menggunakan tribunal atau badan-badan lainnya, yang sering kali dibentuk oleh sistem pemerintahan. Hal-hal ini menunjukkan politisasi pembersihan tersebut. Di seluruh wilayah ini terdapat usaha untuk menggunakan proses persyaratan politik dan penilaian politik, pergeseran menuju proses yang lebih informal, dan memperhatikan pelanggaran politik yang tidak didefinisikan dengan jelas, seperti “pelecehan negara” dan “perendahan negara”.30 Meskipun biasanya hukuman diputuskan berdasarkan pada tindakan melanggar hukum di masa lalu, pelanggaran-pelanggaran baru ini dibuktikan berdasarkan temuan kondisi politik oleh suatu badan yang diberi kekuasaan untuk menemukannya pada masa transisi. Penentuan kolaborasi dan kejahatan politik lainnya dilakukan dengan membuktikan status politik sebagai pendukung doktrin totaliter. Tujuan penyelidikan bukanlah pembuktian tindakan kriminal di masa lalu seperti dalam proses pengadilan, namun keanggotaan atau dukungan terhadap organisasi politik yang “subversif”. Bersama dengan pelanggaran-pelanggaran baru ini, diciptakan pula prosedur, pengadilan, undang-undang dan tindakan khusus untuk mendukungnya.31 Tribunal-tribunal pembersihan bukanlah pengadilan sipil biasa, namun pengadilan militer dan badan administratif lain yang beranggotakan hakim, non-juris dan orang-orang awam. Meskipun hukumannya sering kali berupa sanksi pidana tradisional, sanksi lainnya mempengaruhi status perdata, seperti hilangnya hak memilih dan dipilih, hak partisipasi politik dan bahkan kewarganegaraan. Baik dalam proses maupun dampaknya, ini adalah bentuk keadilan yang di luar kebiasaan. Secara historis, pembersihan dilakukan terhadap para pemimpin rezim lama. Namun dalam pembersihan pasca-perang, hal ini dilakukan secara lebih luas, yang mencerminkan pemahaman yang luas terhadap tanggung jawab dan transformasi. Tindakan-tindakan ini menyingkirkan individu dari segmen masyarakat yang luas, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya tidak dianggap sebagai bagian administrasi, seperti pendidikan dan media. Pembersihan ini dengan demikian merekonstruksi ranah publik, karena berusaha menyusun kembali berbagai sektor: bisnis, media, elite intelektual, yang dengan satu atau lain cara pernah mendukung rezim Nazi. Pembersihan ini merupakan rekonstruksi radikal terhadap berbagai mata pencarian dengan komisi-komisi khusus untuk membersihkan sektor pendidikan, sastra dan musik. Meskipun pembersihan mengatur sektor privat, namun pembersihan itu dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran 30 Lihat misalnya, Ordinance Instituting National Indignity, Prancis, 26 Agustus 1944). Lihat juga Decree of June 27 (Prancis, 1944); Herbert Lottman, The Purge: The Purifucation of French Collaborators after World War II, New York: William Morrow, 1986, 194-210. 31 Lihat Peter Novick, The Resistance versus Vichy: The Purge of Collaborators in Liberated France, New York: Columbia University Press, 1968. 14 dikemukakan secara kabur, dan kelalaian untuk “bersikap secara seharusnya” dalam masa pendudukan menjadikan seseorang dikenakan petanggungjawaban hukum.32 Pembersihan yang paling radikal dan luas terjadi dalam sektor media.33 Dalam kasus ini, kolaborasi mudah dibuktikan – dengan teks sebagai buktinya – dan penerbitan menyebabkan isu kolaborasi ini terlihat di mata publik. Melalui pembersihan, media dijadikan bagian dari rezim baru di mata publik. Ketika media-media kolaborator dibersihkan, batasan kebebasan berekspresi direkonstruksi berdasarkan respon terhadap masa lalu. Bahkan namanama surat kabar mengalami perubahan mendasar, seperti nama surat kabar Prancis, Libération, simbol perubahan identitas. Pembersihan sektor publik pasca-pendudukan ini tidak hanya dilakukan pada sistem layanan publik, namun diusahakan untuk “memurnikan” masyarakat secara keseluruhan. Pembersihan politik dalam sektor publik ini secara kritis merespon sifat represi fasis yang khas, yaitu dengan hegemoni sektor-sektor produksi ideologi, seperti pendidikan dan media.34 Pertanggungjawaban elite intelektual menunjukkan pengakuan terhadap perannya yang menerima fasisme dan usahanya untuk mengarahkan kembali sektor ini ke ideologi rezim penerus yang liberal. Pembersihan pasca-perang merekonstruksi kaitan antara individu, organisasi dan negara. Pelucutan politik ditentukan berdasarkan kolektif, namun mempengaruhi individu. Pendekatan informal dalam proses identifikasi afiliasi fasis masa lalu ini menunjukkan bahwa penyingkiran berdasarkan keanggotaan kelompok tidak diarahkan pada pelanggaran individual. Yang menjadi sasaran adalah perubahan institusional untuk menuju transformasi lingkup publik. Individu menjadi sarana untuk secara publik mengutuk ideologi rezim lama dari ranah publik di masa depan. Pembersihan pasca-perang ini menantang intuisi kita tentang peran hukum, karena pelaksanaan keadilan tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang lazim, namun melalui prosedur informal dan tidak teratur. Ketidaktaatan proses tersebut pada due process, juga sifatnya yang tidak transparan dan terpolitisasi, mencerminkan pemahaman tentang kedaulatan hukum yang dikompromikan. Dan, meskipun tujuannya memandang ke depan, yaitu demokrasi, alat-alat tersebut serupa dengan yang digunakan oleh rezim-rezim represif, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan ideologi, yang bertentangan dengan pemikiran liberal. Meskipun paradoksal, ini adalah respon yang kritis – menggunakan caracara lama secara terbuka untuk menunjukkan pergantian ideologi. Terlebih lagi, masalah yang timbul dari penggunaan cara-cara non-liberal untuk tujuan liberal ini berkurang karena dampaknya yang terbatas pada sistem hukum. Pembersihan pasca-perang ini dilakukan selama waktu yang singkat, dari hanya setahun hingga lima tahun.35 Tindakan yang secara mendasar terpolitisasi ini sejak awal ditujukan sebagai mekanisme transformatif sementara. Sifat sementara yang terlihat di sini, seperti pada contoh-contoh lebih awal, seperti Rekonstruksi Amerika, tampak pula dalam transformasi politik kontemporer yang dibicarakan dalam bab 32 Lihat Henry Lloyd Mason, The Purge of the Dutch Quislings, Den Haag: Nijhoff, 1952, 90. Tentang Prancis, lihat umumnya Novick, Resistance versus Vichy; Lottman, The Purge, 249-63; Tony Judt, Past Imperfect, French Intellectuals, 1944-1956, Berkeley: University of Chicago Press, 1992. Tentang Belanda. lihat umumnya Mason, Purge of the Dutch Quislings. 34 Lihat Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Meridian Books, 1958. 35 Di Prancis misalnya, undang-undang amnesti selektif disahkan pada tahun 1947, dan undang-undang amnesti universal pada tahun 1951. Undang-undang 5 Agustus 1953 menghentikan sanksi administratif. Lihat umumnya Lottman, The Purge. 33 15 ini. Terlihat bahwa respon yang paling terpolitisasi pun sejak awal sudah dirancang untuk bersifat sementara dan merupakan bagian transisi. Lustrace dan Bereinigung: Pembersihan Politik di Eropa Tengah dan Timur Semua orang terlibat dan diperbudak, tidak hanya para pedagang sayur, tetapi juga hingga ke perdana menteri. Posisi yang berbeda-beda dalam hierarki hanya menentukan perbedaan tingkat keterlibatan: si pedagang sayur hanya sedikit terlibat, namun kekuasaannya juga kecil. Tentu saja, perdana menteri memiliki kekuasaan yang besar; ia terlibat secara lebih mendalam. Namun keduanya tidak bebas, masing-masing dengan cara yang sedikit berbeda. Rekanan dalam keterlibatan ini bukanlah seseorang lain, namun sistem itu sendiri. Posisi dalam hierarki kekuasaan menentukan tingkat tanggung jawab dan kesalahan, namun ia tidak membebankan tanggung jawab dan kesalahan yang tidak terbatas bagi seseorang, demikian pula tidak seorang pun benar-benar bebas. (Václav Havel, Open Letters: Selected Writings: 1956-1990) Transisi kontemporer di Eropa Tengah dan Timur pada umumnya merupakan hasil negosiasi, dan dengan demikian bergantung pada tindakan hukum publik radikal untuk melakukan dekomunisasi; hal tersebut menguji peran hukum dalam transformasi politik. Totalitarianisme dicirikan dengan kontrol represif terhadap seluruh masyarakat. Sementara kediktatoran dicirikan oleh adanya garis antara pemerintah dan yang diperintah, dalam totalitarianisme, tidak ada garis yang jelas, dengan represi yang tersebar di seluruh masyarakat. Setelah totalitarianisme, timbul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung-jawab untuk kesalahan di masa lalu. Respon legal terhadap runtuhnya komunisme menunjukkan pemahaman kontemporer tentang tanggung jawab individual terhadap penindasan, kaitan warga negara dengan partai, dan partai dengan negara. Kejahatan pemerintahan totaliter dianggap merajalela, dilakukan oleh suatu pasukan pendudukan dan dengan kolaborasi secara luas. Di seluruh wilayah ini, menyusul perubahan politik, responnya berfokus pada mantan aparat keamanan dan kolaboratornya. Tujuan pembersihan melampaui pemegang kekuasaan resmi; karena pemerintahan totaliter dicirikan oleh penggunaan kekuasaan secara tidak transparan, dan represi yang ambigu entah bersifat privat atau publik. Di seluruh Eropa Tengah dan Timur, mereka yang terkait dengan sistem lama dikenai tindakan pelucutan politik, meskipun tindakan-tindakan dekomunisasi ini bervariasi jangkauan maupun kerasnya. Jerman-bersatu, bekas Cekoslowakia, Bulgaria dan Albania mengesahkan larangan terhadap mantan hierarki Partai Komunis dan aparat keamanan untuk berpartisipasi dalam lingkup publik.36 Hongaria mengambil tindakan yang lebih lunak, seperti penerbitan daftar nama mereka yang terkait dengan pemerintahan komunis. Dalam republik-republik baru ini, diambil tindakan yang melihat ke depan, seperti sumpah kesetiaan. Pemikiran tentang ujian terhadap masa lalu politik diawali secara informal. Pada musim panas 1990, dalam pemilihan umum bebas pertama di bekas Cekoslowakia, partaipartai politik menyaring kandidat mereka dari kaitan dengan aparat keamanan negara. Ketika sebuah komisi parlementer dibentuk untuk menyaring parlemen dari para kolaborator yang 36 Tentang Albania, lihat Human Rights Watch, Human Rights in Post Communist Albania, New York: Human Rights Watch, 1996. Tentang Undang-Undang Panev di Bulgaria, lihat Democracy and Decommunization: Disqualification Measures in Eastern and Central Europe and the Former Soviet Union, 14-15 November 1993, hal. 8-9. 16 terkait dengan aparat keamanan, penyelidikan ini menjadi terpolitisasi. Setahun kemudian, usaha untuk mensistematikkan penyelidikan ini berpuncak pada suatu undang-undang, yang dikenal sebagai “lustrace” atau lustrasi. Lustrasi, yang berasal dari bahasa Latin lustrare, atau “pemurnian”, merujuk pada proses penyelidikan dan penyaringan yang ditujukan untuk mengungkapkan masa lalu. Secara historis, proses penyelidikan demikian terkait dengan melakukan sensus terhadap penduduk.37 Undang-undang lustrasi Cekoslowakia melarang orang-orang yang terkait dengan aparat keamanan negara untuk menduduki banyak jabatan dalam pemerintah, angkatan bersenjata, parlemen, pengadilan, BUMN, akademia dan media. Menurut undang-undang ini, keanggotaan dalam aparat keamanan negara sudah cukup untuk menyatakan bahwa orang tersebut terlibat dalam sasaran represif organisasi tersebut.38 Dengan demikian, undang-undang tersebut mengkodifikasi asumsi bahwa para pendukung rezim komunis membahayakan demokrasi. Undang-undang lustrasi ini ditentang di pengadilan oleh 99 anggota parlemen yang telah tidak menyepakatinya di Parlemen. Penentang lain meliputi organisasi hak asasi manusia, Komisi Buruh Internasional, dan Presiden Václav Havel sendiri, yang menyarankan untuk mengubah rencana tersebut agar memungkinkan penyelidikan individual.39 Dalam keputusannya yang paling kontroversial, Pengadilan Konstitusional menegaskan keberlakuan lustrasi, meskipun membatasi lingkupnya.40 Dekomunisasi juga dimulai secara informal di Jerman-bersatu, dengan pemilihan umum pertama di bekas Republik Demokrasi Jerman. Sementara dalam transisi yang dinegosiasikan lainnya di wilayah ini, pembersihan komunis tampaknya didukung oleh konsensus sosial dalam cabang-cabang politik, di Jerman-bersatu, pembersihan ini dimulai sebagai bentuk “keadilan sang pemenang”. Bagi pihak Timur, tidak banyak pilihan dalam hal ini. Seperti juga Konfederasi ketika hendak memasuki kembali Serikat (Amerika Serikat), ketika Jerman Timur hendak bergabung dengan Jerman-bersatu, hal tersebut disyaratkan dengan penolakan terhadap masa lalu ideologisnya. Negara ini menjadi terbelah karena penyatuannya,41 karena Traktat Unifikasi menentukan syarat-syarat untuk reunifikasi, yang menyatukan layanan publik Jerman, menciptakan sistem penilaian terhadap mereka yang pernah bekerja dalam sistem administrasi Jerman Timur, dan mendiskualifikasi mereka yang 37 Lihat OED, entri “lustration”. Screening (“Lustration”) Law, Akta No. 451/1991 (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1991), disahkan oleh dewan kedua negara federal tersebut. Berdasarkan bagian 22, akta tersebut mulai berlaku sejak disahkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1996. 39 Terdapat banyak kritikan terhadap Undang-Undang Lustrasi. Lihat Stephen Engelberg, “The Velvet Revolution Gets Rough”, New York Times Magazine, 31 Mei 1992, hlm. 30; “Prague Approves Purge of Former Communists”, New York Times, 7 Oktober 1991; Aryeh Neier, “Watching Rights”, The Nation, 13 Januari 1993, hal. 9; Jeri Laber, “Witch Hunt in Prague”, New York Review of Books, 23 April 1992, hlm. 5; “Letters Human Rights in Prague”, New York Review of Books, 28 Mei 1992, hlm. 56; Mary Battiata, “East Europe, Hunts for Reds”, Washington Post, 28 Desember 1991; Lawrence Weschler, “The Velvet Purge: The Trials of Jan Kavan”, New Yorker, 19 Oktober 1992, hlm. 66; John Tagliabe, “Prague Turns on Those Who Brought the Spring”, New York Times, 7 Januari 1992, rubrik Internasional; “The Perils of Lustration”, New York Times, 7 Januari 1992, halaman editorial. Dalam Czech English Language Press, Bill Hungrey, Jr., “Tempest over Lustration”, Prague Post, 17-23 Maret 1992. 40 Specifying Some Further Perequisites for the Discharge of Some Functions in State Organs and Organizations, Akta No. 451/1991 (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1991). 41 Komentar dari Wolfgang Nowak, Sekretaris Negara Urusan Pendidikan Provinsi Sachsen (Jerman Timur), Rapporteur’s Report (dipresentasikan kepada The Foundation for a Civil Society, Venesia, Italia, 1993), 7. 38 17 menjabat dalam hierarki partai Komunis, dan juga Stasi, polisi rahasia yang ditakuti.42 Traktat Unifikasi memungkinkan diskualifikasi atas dua dasar: “tidak dapat diterima karena kelakuan politik di masa lalu” dan “inkompetensi teknis”. Seperti dalam denazifikasi pasca-perang, sekali lagi kuesioner digunakan untuk menentukan orang-orang yang menjadi anggota polisi rahasia, dan komisi lokal diberi hak untuk melakukan pengucilan. Pengesahan Akta Arsip Stasi pada tahun 1991 memungkinkan akses terhadap arsip bekas polisi rahasia dan pengecekan terhadap latar belakang rezim lama, yang berakibat pada pembersihan besarbesaran mantan pejabat sipil Jerman Timur di semua tingkat. Pengucilan dari jabatan publik, keamanan negara dan pendidikan berarti ribuan pejabat, hakim, guru dan pengajar universitas dipecat. Dekomunisasi di Cekoslowakia tampaknya mencakup sasaran yang lebih luas, karena undang-undangnya mencakup hingga jajaran terbawah pendukung rezim lama. Bahkan mencakup mereka yang mengikuti sekolah keamanan atau sebagai “kandidat” kolaborator, sehingga berpotensi mempengaruhi puluhan ribu orang. Terlebih lagi, pelaksanaan lustrasi Cekoslowakia dilakukan oleh Kementerian dalam Negeri secara tersentralisasi, sementara pembersihan Jerman dilakukan pada tingkat lokal. Namun pada akhirnya, pembersihan Jerman memiliki dampak yang lebih luas, karena mereka diterapkan secara sistematis oleh aparat administratif yang sudah ada dan berfungsi penuh, dan pengganti pejabat yang dipecat telah tersedia. Penggunaan pelucutan politik yang luas dijustifikasi hanya oleh kaitan atara afiliasi politik masa lalu dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam rezim demokratik. Namun, skema demikian menimbulkan pertanyaan normatif: apa relevansi antara perilaku politik di masa lalu dengan terbentuknya tatanan politik baru. Baik di bekas Cekoslowakia dan Jerman, pertanyaan ini kontroversial dan berakhir pada pada tinjauan konstitusional. Tinjauan konstitusional memerlukan justifikasi publik yang berlanjut terhadap kebijakan dekomunisasi. Di Jermanbersatu, diskualifikasi politik dijustifikasi oleh asumsi bahwa seorang mantan komunis tidak bisa bertugas dalam sistem politik yang demokratis. Di negara-negara lain, seperti Hongaria, diskualifikasi politik serupa dijustifikasi oleh badan peradilan atas alasan demokrasi.43 Dalam menegaskan konstitusionalitas lustrasi, Pengadilan Konstitusional Republik Federal Ceko dan Slowakia menganalogikan hal tersebut dengan security clearance (bukti kelakuan baik) dalam sistem demokrasi yang mapan. Seperti security clearance, lustrasi menjadi syarat pekerjaan berdasarkan kelakuannya di masa lalu, hukum tersebut “hanya menunjukkan beberapa syarat tambahan untuk jabatan-jabatan sensitif tertentu dalam administrasi negara dan aparat ekonomi”. Mengizinkan “orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran atau penindasan hak asasi manusia dan kebebasan ... cara-cara yang memberi peluang bagi destabilisasi serius terhadap perkembangan demokrasi dan mengancam keamanan warga negara mendatangkan risiko yang besar”.44 Bandingkanlah analogi kebijakan lustrasi dalam masa transformatif dengan peran security clearance dalam negara-negara yang 42 Provisi diskualifikasi Jerman dapat dilihat dalam Traktat Unifikasi 31 Agustus 1990. Lihat Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman, “Agreement with Respect to the Unification of Germany”, 31 Agustus 1990, BGB1.II, diterjemahkan dan dicetak ulang dalam International Legal Materials 30 (1991): 457 (kemudian “Traktat Unifikasi Jerman”). 43 Lihat Decision No. 1, Constitutional Case No. 32 (Hungaria, 1993). Dekomunisasi juga dijustifikasi atas alasan keamanan. 44 Constitutional Court Decision on the Screening Law, Ref. No. P1. US1/92, (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1992). 18 sudah mapan. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, pembuktian bahwa seseorang dapat dipercaya, sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan, biasanya dibatasi pada posisiposisi yang berkaitan dengan keamanan atau posisi yang sensitif, yang memiliki akses terhadap informasi rahasia. Biasanya, hanya sedikit posisi publik yang membutuhkan keamanan lebih tinggi; diskualifikasi demikian biasanya dianggap tidak dapat dijustifikasi dan bersifat punitif. Lebih lagi, pemerintah dalam kondisi biasa menanggung beban untuk menunjukkan relevansi proses penyaringan dengan posisi yang terkait. Analogi dengan security clearance ini bisa menjustifikasi penyaringan untuk posisi-posisi tertentu dalam pemeritahan di wilayah ini, seperti yang berkaitan dengan hak asasi manusia; dan kepentingan hak asasi manusia bisa menjustifikasi bentuk pendahuluan terhadap undang-undang lustrasi, yang akan menyaring mereka yang bertanggung-jawab secara pribadi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kepentingan keamanan tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi luasnya lingkup lustrasi. Dalam sejarah, negara memiliki kekuasaan besar untuk mensyaratkan hak untuk memegang jabatan atas dasar politik. Dalam hukum Konstitusional Amerika, misalnya, hal ini tampak dalam opini yudisial penting bahwa “seseorang bisa memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang politik, namun ia tidak memiliki hak konstitusional untuk menjadi seorang polisi”.45 Namun, pandangan modern telah bergeser dari pandangan historis ini. Meskipun syarat politik terhadap praktik hukum berkaitan dengan keanggotaan partai komunis pada suatu waktu diterapkan, hal ini terjadi pada masa Perang Dingin, dan hukum Amerika telah berubah.46 Sistem demokrasi liberal modern biasanya tidak diizinkan mengambil keputusan dalam ranah publik semata-mata atas pertimbangan politis. Dalam sistem demokrasi yang mapan, hanya posisi puncak pemerintahan yang pengangkatannya dijustifikasi melalui dasar politik, atau dengan proses pemilihan umum. Meskipun hak untuk memegang jabatan publik atau mendapat layanan publik bisa dikekang, biasanya negara tidak berhak untuk melakukan hal tersebut atas dasar politik. Dalam negara liberal, syarat politik harus dijustifikasi oleh kepentingan yang signifikan dan terkait erat dengan usaha memajukkan kepentingan tersebut. Kepentingan efisiensi pemerintahan biasanya dianggap tidak cukup untuk menjustifikasi penunjukkan posisi secara politis.47 Loyalitas politik pun tidak cukup untuk menjustifikasi politik patronase. Relevansi afiliasi politik bergantung pada sifat afiliasi ini yang menjadi dasar diskualifikasi. Ia juga bersyarat pada pemerintah yang menunjukkan kaitan erat antara posisi yang dipermasalahkan dan dasar politik, dengan afiliasi politik menjadi pertimbangan hanya bila relevan pada efektivitas kinerja.48 Prinsip umum yang menentang pengambilan keputusan secara politis dalam lingkup publik melindungi hak organisasi politik dan hak untuk berpendapat bebas, yang penting dalam sistem demokrasi.49 Lebih lanjut lagi, dalam sistem demokrasi berkeadilan sosial di Eropa yang dicirikan oleh pengaturan pekerjaan yang lebih 45 McAuliffe v. City of New Bedford, 29 NE 517 (Mass. 1892). Lihat Elfbrandt v. Russel, 384 US 11 (1966). Lihat juga Branti v. Finkel, 445 US 507 (1980) (menolak pencopotan berdasarkan afiliasi atau dukungan partai) (menolak persyaratan menjadi pegawai negeri akibat keanggotaan partai komunis). 47 Lihat Elrod v. Burns, 427 US 347 (1976). 48 Lihat United States v. Robel, 389 US 258, 166 (1967); Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 US 62, 70-71 (1990). Lihat juga Konigsberg v. State Bar, 366 US 36 (1961); In re Anastapolo, 366 US US 82 (1961). 49 Lihat PBB, Sidang Umum, Universal Declaration of Human Rights, A/RES/217A (III), 10 Desember 1948, Pasal 2. 46 19 besar, kondisionalitas politik akan mempengaruhi hak-hak lain seperti hak sebagai pekerja dan kebebasan dalam lingkup publik.50 Meskipun intuisi biasa tentang kedaulatan hukum akan mendorong penolakan terhadap tindakan politik demikian, kepentingan transisional tertentu bisa mendukung pengambilan tindakan seperti itu pada masa-masa yang terbatas. Maka, dengan mengesahkan kebijakan penyaringan, Pengadilan Konstitusional bekas Cekoslowakia merasionalkan kebijakan lustrasi atas dasar kebutuhan luar biasa masa tersebut. Dengan memperingatkan “kemungkinan kemunduran ke masa-masa pemerintahan totaliter” dan kebutuhan untuk mencegah “destabilisasi perkembangan demokrasi negara”, justifikasi pengadilan untuk kebijakan ini jelas-jelas bersifat transisional. Langkah-langkah ini dijustifikasi oleh kebutuhan membangun rezim yang lebih demokratis: Semua negara, terutama yang telah mengalami penderitaan karena pelanggaran hak-hak dan kebebasan asasi oleh kekuasaan totaliter selama lebih dari empat puluh tahun memiliki hak untuk menerapkan tindakan legislatif demikian yang berusaha untuk mencegah risiko subversi berupa kembalinya rezim totaliter, untuk menciptakan sistem demokratis. Preseden transisional lainnya dari masa pasca-perang juga dijadikan pertimbangan: “Tindakan-tindakan demikian ... juga diambil oleh negara-negara Eropa lainnya setelah runtuhnya rezim totaliter ... sebagai cara yang sah ... bukan untuk mengancam karakter demokratik sistem konstitusional ... atau ... hak hak dan kebebasan warga negara ... namun untuk perlindungan dan konsolidasinya”.51 Bahwa justifikasi luar biasa untuk pelucutan politik dibatasi pada jangka waktu yang terbatas selama pergeseran politik diakui dalam hukum tersebut, yang di dalamnya terdapat pembatasan waktu. Di bekas Cekoslowakia, meskipun lustrasi pada awalnya diharapkan untuk berlangsung selama lima tahun, di Republik Ceko, hal ini diperpanjang lima tahun lagi. Pelucutan politik di Jerman-bersatu juga secara eksplisit bersifat sementara sejak awalnya.52 Keterlibatan dalam rezim politik lama sering kali dianggap berpengaruh pada kedudukan sebagai pejabat publik dalam masyarakat transisional selama masa-masa transformasi politik yang rapuh dari pemerintahan represif ke liberal. Namun apa batasan relevansi kesetiaan politik masa lalu? Secara historis, setelah kediktatoran berakhir, pembersihan dilakukan terhadap jajaran tertinggi posisi politik. Namun, pembersihan setelah 50 Lihat Pasal 2(7), “International Covenant on Civil and Political Rights”, 6 Desember 1966, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 999, No. 14668 (1976): 171; Pasal 2(2), “International Covenant on Economic, Social and Cultutal Rights”, 16 Desember 1966, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 993, No. 14531 (1976): 3. Lihat juga 7(c), “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” melindungi “kesetaraan kesempatan” dalam memperoleh pekerjaan. 51 Constitutional Court Decision on the Screening Law (Republik Federal Czek dan Slowakia, 26 November 1992). Lihat juga K. 3/98 Judgment in the Name of the Republic of Poland Constitutional Court on the Incompatibility of Law of 17.12.97 on Amendments of the Law on Judicial System and some other Statutes with the Constitutions of the Republic of Poland of 02.04.87. Seperti dikatakan oleh pengadilan dalam Judgment of 3/98, “suatu transisi dari negara otoriter ke demokrasi bisa secara luar biasa mencapai solusi yang tidak akan dijustifikasi dalam kondisi normal”. 52 Kemudian, undang-undang Ceko ini diperpanjang masa berlakunya hingga tahun 2000. Lihat Jirina Siklova, “Lustration or the Czech Way of Screening”, East European Constitutional Review 5, No. 1 (musim dingin 1996): 59. Lihat juga “Constitution Watch”, East European Constitutional Review 4 (musim gugur 1995): 8-10. Tentang peamahaman Jerman, lihat “Traktat Unifikasi Jerman”. 20 runtuhnya komunisme merespon bentuk represi yang lain, yaitu pemerintahan totaliter yang berkaitan dengan semua sektor masyarakat, di mana semua orang terlibat. Sifat represi totaliter mungkin dapat menjustifikasi pembersihan satu generasi politik secara keseluruhan, dan timbul pertanyaan tentang dari mana menarik batasannya. Bagi beberapa pemikir, diperlukan status yang tidak kurang dari oposan untuk menunjukkan integritas moral yang diperlukan untuk memegang jabatan publik tingkat tinggi dalam rezim yang baru. Dalam gelombang perubahan politik kontemporer, status oposan menjadi syarat de facto jabatan tinggi politik. Dalam banyak administrasi transisional di Eropa Timur dan Amerika Latin, presiden yang baru adalah mantan oposan. Contohnya adalah Václav Havel di bekas Cekoslowakia, Arpad Göncz di Hongaria, Lech Walesa di Polandia. Di Amerika Latin, Presiden Carlos Menem sempat dipenjarakan pada masa pemerintahan militer sebelumnya. Presiden Brazil Fernando Cardoso adalah seorang pelarian politik selama masa pemerintahan militer di negara itu. Mantan presiden Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada juga berasal dari keluarga yang sempat mengalami pengasingan. Namun sejauh mana perlu digunakan garis pemikiran ini? Selain pada tingkat kepemimpinan tertinggi, sejauh mana keterlibatan dalam kesalahan rezim lama berkaitan dengan kesempatan memegang jabatan publik dalam rezim liberal? Apakah ada prinsip kedaulatan hukum yang memandu pembersihan transisional dan menjustifikasi pengambilan keputusan yang dipolitisasi? Pertanyaan ini menjadi pertimbangan Pengadilan Konstitusional bekas Cekoslowakia, ketika ia meninjau undang-undang lustrasi dan pengaruhnya bagi banyak orang yang tampil dalam arsip polisi rahasia sebagai kandidat kolaborator yang potensial. Puluhan ribu orang termasuk dalam kelompok ini, dan hanya sebagaian kecil yang sukarela secara sadar bersedia berkolaborasi dengan rezim lama. Keanggotaan tanpa sadar demikian, menurut pengadilan, tidak cukup untuk mendiskualifikasikan mereka dari tatanan politik yang baru.53 Paling tidak, ditarik garis pada “keanggotaan secara sadar”. Pertanyaan kedua yang dihadapi kebijakan dekomunisasi adalah apakah keanggotaan secara sadar demikian cukup menjadi dasar untuk penyingkiran mereka. Pertanyaan ini timbul dalam suatu kasus yang dibahas dalam undang-undang diskualifikasi Jerman-bersatu.54 Untuk menjustifikasi pengucilan politik, keterlibatan demikian harus lebih dari sekadar keanggotaan secara sadar, yang merupakan hal umum dalam sistem kemasyarakatan Jerman Timur. Sebagai masalah konstitusional, menurut pengadilan tersebut, kesesuaian untuk posisi jabatan publik tidak bisa ditentukan semata-mata dengan dasar posisi dalam hierarki Jerman Timur atau identifikasi dengan rezim Partai Serikat Buruh Jerman (SED). Karena “loyalitas kepada pemerintahan sosialis ... [merupakan suatu] yang harus ada untuk menduduki jabatan publik di Jerman Timur ... loyalitas dan kerja sama yang merupakan hal yang diperlukan untuk tetap bertahan dan menanjak dalam karier publik ... tidak bisa menjadi justifikasi satu-satunya”.55 Apakah seseorang tepat untuk menjabat dalam sistem layanan yang baru perlu dijustifikasi berdasarkan kondisi khusus, kasus demi kasus. Dalam kasus-kasus serupa, kedaulatan hukum yang digunakan oleh pengadilan mendukung prinsip liberal bahwa hukum publik harus dikonstruksikan tidak hanya sesuai dengan ideologi politik, namun dengan sesuatu yang melampauinya. 53 Lihat Constitutional Court Decision on the Screening Law. Lihat Act Concerning the Records of the State Security Service of the Former German Democratic Republic (Jerman, 1991) (“Akta Arsip Stasi”). Lihat juga “Traktat Unifikasi Jerman”. 55 Judgment by First Senate of Constitutional Court (Jerman, 1955) (terjemahan penulis). 54 21 Bila undang-undang yang menyusun sistem peradilan suksesor akan mendiskualifikasi badan peradilan yang sudah ada atas dasar “pengambilan keputusan yang dipolitisasi pada masa rezim sebelumnya”, syarat politik ini, menurut pengadilan konstitusional, terlalu kabur untuk diterapkan.56 Pengadilan Konstitusional Polandia menempatkan batasan kedaulatan hukum terhadap lustrasi terpolitisasi berskala besar terhadap badan peradilan negara tersebut. Dalam meninjau sebuah kasus tentang mantan kepala polisi, Pengadilan Konstitusional Jerman membatalkan pemecatannya karena inkonstitusional, menentang kebijakan dekomunisasi. Dengan membela prinsip tinjauan yudisial, pelucutan politik antikomunis dianggap sebagai asumsi legislatif yang tidak kompeten, namun bukan berarti tidak dapat dibantah. Pengadilan melakukan penyelidikan tidak hanya terhadap kelakuan di masa lalu untuk menentukan prospek individual para mantan pejabat, untuk tetap menduduki jabatannya dalam rezim demokratik. Dalam kasus polisi tersebut, terdapat bukti bahwa ia bisa memperbaiki dirinya, sehingga layak bertugas dalam rezim demokratik. Potensi reformasi ini tampak penting dalam konteks Jerman, di mana terdapat inkorporasi Jerman Timur ke dalam struktur demokratis yang sudah ada, sehingga tidak ada justifikasi untuk penyingkiran secara luas. Dengan mengakui garis dasar afiliasi politik dengan rezim totaliter di masa lalu, diciptakan batasan afiliasi politik masa lalu yang dapat diterima. Bila terdapat dukungan luas dari masyarakat terhadap suatu rezim, dukungan demikian tidak cukup untuk mendiskualifikasi satu generasi politik. Prinsip normatif ini memandu kaitan dengan masa lalu dalam transisi setelah komunisme. Kasus polisi tadi menunjukkan potensi pengadilan konstitusional dalam masa-masa gejolak politik. Ketika ia menolak asumsi legislatif tersebut, Mahkamah Agung Jerman menegaskan prinsip utama dalam demokrasi liberal, yaitu perlindungan hak individual dalam sistem tinjauan yudisial. Jika pemerintahan totaliter dicirikan dengan luasnya penetrasi hingga ke lingkup privat, suatu badan peradilan yang independen menjadi tumpuan harapan liberal untuk membatasi kekuasaan negara. Pertimbangan dalam kasus ini menunjukkan kaitan keadilan transisional dengan sejarah masa lalu. Setelah pemerintahan represif berakhir, restrukturisasi sistem layanan publik berarti merekonstruksi kaitan normatif antara individu dan tatanan politik. Namun apa relevansi perilaku politik masa lalu dengan pembuatan keputusan publik pada rezim transisional, bila hal-hal lain juga berubah? Perubahan pada tingkat individu harus diperhatikan dalam kerangka perubahan struktural yang lebih luas. Dengan perubahan dalam konteks politik dan pergeseran sistem politik, perilaku individu di masa lalu tidak relevan terhadap prospek demokrasi suatu masyarakat. Namun, selama logika persyaratan politis ini dijustifikasi dengan memandang ke depan, justifikasi demokrasi ini tampaknya tidak koheren: menentukan persyaratan politik individu berdasarkan kelakuannya di masa lalu tidak mendukung potensi terciptanya institusi politik baru. Dengan demikian, keadilan transisional tidak dapat direduksi dengan mudah, karena ia merespon kondisi-kondisi politik sekaligus peninggalan sejarah pemerintahan represif yang khas. Keadilan Administratif dan Distributif 56 Lihat Akta 29 April 1985 mengenai Tribunal Konstitusional, diamendemen oleh Akta Tribunal Konstitusional 1 Agustus 1997. 22 Pada umumnya, skema-skema politis yang dibicarakan di sini dijustifikasi atas dasar demokrasi untuk mengkonstruksi suatu tatanan politik baru. Namun, ada pula tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai masyarakat transisional dengan menata ulang layanan publik atas dasar politik, antara lain redistribusi. Pelucutan politik terhadap kelompok yang dibicarakan di atas mengoperasionalkan prinsip distributif untuk partisipasi politik atas dasar preferensi sistem poltitik. Misalnya, dekomunisasi atau diskualifikasi politik serupa dapat direkonseptualisasikan sebagai skema preferensi masif berdasarkan afiliasi politik. Argumen demikian diajukan dalam transisi di Afrika Selatan pasca-apartheid.57 Syarat politik dapat dianggap sebagai preferensi. Apa justifikasi untuk keputusan kolektif atas dasar politik, seperti “affirmative action”? Bila sistem politik mengalami liberalisasi, kepentingan negara apakah yang menjustifikasi preferensi remedial atas dasar ketaatan politik? Preferensi transisional bisa dianalogikan dengan sistem patronase dalam demokrasi di masa lalu. Sementara kini terdapat prinsip anti-diskriminasi, dalam sejarahnya, patronase digunakan untuk mengorganisir sistem administrasi publik. Setelah Perang Dunia Kedua, diskriminasi oleh pemerintah atas dasar politik mengingatkan orang pada penindasan di masa lalu, sehingga dihilangkan dalam hampir semua hukum domestik dan internasional. Hampir semua perundang-undangan hak asasi manusia internasional pasca-perang menjamin perlindungan yang setara tanpa memandang afiliasi politik. Prinsip anti-diskriminasi menyatakan bahwa bila perundang-undangan melakukan diskriminasi atas dasar opini politik, harus ada kepentingan pemerintah yang amat besar. Dalam kondisi biasa, legitimasi konstitusional atas pelucutan politik demikian akan bergantung pada sifat justifikasi negara tersebut, tentang apakah ada kepentingan negara yang menjustifikasi pengabaian prinsip kesetaraan ini. Dari perspektif ini, pelucutan politik anti-komunis di Eropa Timur sering kali dirasionalisasi sebagai suatu bentuk affirmative action.58 Argumennya adalah sebagai berikut: di Eropa pasca-komunis, menjadikan ketaatan pada sistem politik relevan dengan partisipasi dalam administrasi negara di masa depan tidak hanya berarti memberikan beban pada kebebasan beropini politik pada masa kini, namun juga memikul beban sejarah. Dalam transisi kontemporer, preferensi politik dijustifikasi, karena seperti masalah preferensi rasial di Amerika Serikat peninggalan sejarah sistem politik di Eropa Timur memiliki peran yang memecah belah dan menindas dalam sejarah wilayah ini. Bagaimanapun bentuk komitmen terhadap kesetaraan politik dalam rezim penerus, konteks sejarah untuk pembersihan sejarah di wilayah ini adalah masa-masa diskriminasi politik yang panjang. Bahkan, signifikansi diskriminasi politik dalam sejarah ini diakui oleh pengadilan konstitusional di wilayah ini dalam tinjauan mereka tentang tindakan penyaringan transisional. Dalam membela kebijakan lustrasi, pengadilan konstitusional Republik Ceko menyatakan: Sebuah negara demokratik ... tidak bisa tinggal diam bila semua posisi tertinggi dijabat berdasarkan kriteria politik. Sebuah negara demokratik wajib berusaha untuk menghilangkan preferensi yang tidak terjustifikasi terhadap sekelompok tertentu warga negara, berdasar pada prinsip keanggotaan pada partai politik tertentu, dan juga melenyapkan diskriminasi terhadap warga negara.59 57 Lihat “Peace for Affirmative Action” New York Times, 21 Februari 1998, hal. A2. Untuk analisis kritis, lihat John Elster, “On Doing What One Can”, East European Constitutional Review 1 (1992): 15. 59 Constitutional Court Decision on the Screening Law. 58 23 Diskriminasi politik di masa lalu menarik untuk digunakan sebagai justifikasi, namun ia tidak cukup untuk menjustifikasi diskriminasi politik di masa kini. Sementara skema dekomunisasi memiliki arti perpindahan dari orang-orang komunis ke non-kominis, skemaskema demikian tidak dirancang untuk mendorong keberagaman politik dalam sistem demokrasi yang baru tumbuh. Hingga sejauh mana analogi affirmative action diperlakukan secara tidak adil? Apakah bisa dikatakan bahwa mungkin terdapat “orang-orang benar” yang diperlakukan secara tidak adil? Tidak semua jabatan publik di masa lalu dirampas secara tidak adil dari orang-orang non-komunis; tidak semua orang yang bekerja di masa tersebut memegang jabatannya secara curang. Tindakan dekomunisasi yang melarang orang untuk bekerja dalam sektor publik ditentang karena melanggar hak-hak individual, seperti hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan.60 Namun, tantangan ini pun kontroversial, karena perubahan politik berjalan bersama dengan perubahan ekonomi dan sistem layanan publik. Apakah pelucutan politik mengancam hak untuk bekerja, dan bagaimana caranya, menjadi pertanyaan kontroversial tentang pemahaman sosial dalam transisi menuju sistem pasar. Kepentingan redistributif yang memandang ke depan digunakan untuk menjustifikasi perundang-undangan diskualifikasi secara luas yang menghukum orang-orang komunis dan menguntungkan orangorang non-komunis. Ketika kategori politik ditarik ulang, untuk mencabut preferensi masa lalu sehingga menguntungkan oposisi politik, kepentingan negara dalam redistribusi sektor publik tampak tidak saja diskriminatoris secara politis namun juga memiliki tujuan terselubung. Perundang-undangan dekomunisasi memandang ke depan dan sekaligus ke belakang dalam masa transisi. Hak-hak dari masa lalu digunakan untuk menjustifikasi realokasi pekerjaan dalam rezim penerus. Redistribusi transisional ini merekonstruksi cara-cara penentuan hak di muka, dan mendefinisikan ulang kaitan sosial dalam sistem lama, yaitu sebuah sistem yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hak properti. Interaksi kriteria keadilan transisional dan distributif dalam pengembalian hak-hak mereka yang semula dirampas kesempatannya akan dibahas dalam bab berikut. Menarik-Ulang Garis Partai: Arti Sosial Pembersihan dalam Sektor Publik Pembersihan secara publik mengkonstruksi transformasi sosial dengan mendefinisikan kembali batasan lingkup politik, sebagai batas pelucutan politik dalam sektor publik. Hal ini meruakan dampak dari transisi. Sebagian besar dampak dekomunisasi adalah dari pengungkapan kolaborasi di masa lalu melalui publikasi dan pertanggungjawaban politis serta sanksi sosial.61 Meskipun larangan bekerja bisa dicabut setelah waktu tertentu, tidaklah demikian dengan stigma “musuh demokrasi”. Di bekas Cekoslowakia, daftar “orang-orang yang disingkirkan” yang dibacakan di televisi menimbulkan gejolak sosial; di Polandia, pembocoran nama-nama mengakibatkan krisis politik yang nyaris menjatuhkan pemerintah. Begitulah, lustrasi diawali sebagai pengungkapan secara de facto di muka umum; dan bahkan bila diatur oleh hukum, pada akhirnya undang-undang tetap tidak menggunakan sanksi 60 Lihat misalnya, International Labour Organization Decision on the Screening Law, GB. 252/16/19 (Republik Federal Czek dan Slowakia, 1992). 61 Lihat Act on the Illegality of the Communist Regime and Resistance to It, Akta No. 198/1993 (Republik Czek, 1993). 24 tradisional yang diasosiasikan dengan hukum, dan bergantung pada pengeksposan di lingkup publik. Sebagai contoh, di Hongaria, daftar nama-nama yang dianggap terlibat dalam represi di masa lalu diterbitkan di harian para pegawai negeri. Lustrasi Cekoslowakia juga bersifat deklaratoris. Dalam tinjauannya terhadap UndangUndang Ilegalitas Rezim Komunis, Pengadilan Konstitusional secara gamblang mengakui dan menegaskan sifat perundang-undangan dekomunisasi: Undang-Undang Lustrasi tersebut, tidak memberikan sanksi, namun ia hanya menentukan syarat untuk memegang jabatan tertentu ... Dasar konstitusional bagi negara demokratis tidak menghalangi parlemen untuk menyatakan ... sudut pandang moral dan politisnya dengan cara yang tepat dan dapat diterima dalam batasan prinsip-prinsip umum hukum dalam bentuk yang bisa disahkan sebagai statuta.62 Dengan merujuk pada fungsi hukum yang “memuji” dan “menyalahkan”, undang-undang ini diharapkan berfungsi sebagai cara deklaratoris normatif. Meskipun tidak secara formal menunjukkan tanggung jawab pidana, namun ia mendorong pengutukan sosial yang kerap dikaitkan dengan putusan pidana. Dalam aspek stigmatisasinya, dampak lustrasi berpotensi serupa dengan perundang-undangan pidana.63 Dalam kondisi biasa, stigma demikian akan didukung dengan penunjukkan tanggung jawab individual yang merupakan ciri proses pidana. Pengucilan politik ini menimbulkan perhatian pada signifikansi pengumuman nama: pembersihan dimulai dari daftar ini. Ketika daftar mereka yang harus disingkirkan itu terbit, daftar itu sendiri merupakan suatu bentuk putusan politik yang menimbulkan stigma. Mungkin pendekatan paling tidak formal terhadap lustrasi dilakukan di Polandia, di mana kandidat untuk posisi tinggi diharap menunjukkan bahwa ia “bersih diri” dengan mengumumkan kaitan mereka dengan polisi rahasia antara tahun 1944 dan 1990.64 Undang-undang dekomunisasi mengungkapkan secara gamblang makna sosial tindakan regulatoris yang tidak terdapat dalam sanksi formal, perubahan hak atau kewajiban yang secara umum dikaitkan dengan hukum. Dengan melihat konteks peninggalan sejarah di wilayah ini, pembersihan politik dalam lingkup publik memiliki makna. Bagaimana tepatnya cara, syarat dan pelucutan politik memungkinkan transformasi? Pembersihan oleh rezim penerus dilakukan untuk membongkar represi rezim lama, hukum digunakan untuk merekonstruksi kelompok-kelompok politik yang relevan terhadap partisipasi dalam lingkup publik. Dalam masa transisi, rezim penerus menggunakan kategori-kategori politik yang dahulunya dipakai untuk menjadi persyaratan dalam rezim lama, untuk melakukan diskualifikasi. Kekuatan rekonstruksi politik menjadi terlihat jelas dengan latar belakang ini; pembersihan pasca-komunis bersifat performatif karena mereka dengan eksplisit membalikkan dasar proses yang semula mendukung rezim lama. Namun, kebergantungan pada dokumentasi milik rezim lama memiliki dampaknya sendiri. Penilaian terhadap masa lalu seseorang dilakukan dengan merujuk pada arsip-arsip rezim lama; dengan arsip-arsip tersebut sebagai ujian politik. “Lustrasi” atau verifikasi dilakukan melalui arsip-arsip ini; kebenaran ditemukan dari catatan milik rezim lama. 62 Constitutional Court Decision on the Act on the Illegality of the Communist Regime 1993 (Republik Czek, 1993). 63 Lihat umumnya Dan M. Kahan, “What do Alternative Sanctions Mean?” University of Chicago Law Review 63 (1996): 591. 64 Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, New York: Macmillan, 1968. 25 Dalam pergantian administrasi biasa di negara-negara demokrasi normal, kebergantungan pada arsip rezim lama bukanlah hal yang luar biasa; namun dalam pergeseran antara sistem politik, terutama dari kediktatoran ke sistem-sistem yang lebih liberal, kebergantungan pada arsip lama memiliki arti mempertahankan kontinuitas dalam dasar material rezim lama, dan dengan demikian menjadi amat paradoksal. Ini terjadi karena usaha untuk membersihkan masa lalu dilakukan dengan proses-proses yang amat terkait erat dengan masa lalu itu sendiri. Bahkan istilah yabng digunakan merujuk pada proses-proses dalam rezim lama. “Lustrasi” adalah istilah yang digunakan polisi rahasia Cekoslowakia untuk penilaian latar belakang loyalitas warga negara terhadap partai komunis selama pemerintahannya yang berlangsung selama 40 tahun. Dengan menggunakan sudut pandang ini, pembersihan pasca-1989 hanyalah pembersihan terbaru dalam seperangkat pembersihan: antara lain pembersihan yang dilakukan pada tahun 1970; pembersihan para reformis 1968, ketika setengah juta orang dipecat dari partai; dan sebelumnya, tahun 1948 dan pembersihan Stalinis.65 Bahkan dalam bentuknya yang lunak, lustrasi mengingatkan kembali pada rezim totaliter. Dengan demikian, ia merekonstruksi masyarakat dengan cara lama, dengan mendefinisi-ulang partai politik melalui cara yang sama. Lustrasi tampak terkait erat dengan rezim lama, bahkan sementara ia digunakan untuk tujuan transformatif. Jika bab ini diawali dengan mempertanyakan kaitan cara-cara non-liberal terhadap tujuan liberal, pembersihan politis di Eropa Timur dan Tengah menunjukkan masalah tersebut. Di sini terdapat paradoks konstruksi sosial dekomunisasi dalam transisi, tentang pembersihan politik yang mengutuk kejahatan masa lalu, namun sekaligus menggunakan cara-caranya. Dalam negara-negara demokrasi baru, undang-undang dekomunisasi mengingatkan kembali pada masa lalu totaliter mereka. Hingga titik tertentu, penggunaan bentuk-bentuk demikian akan mengingatkan orang pada represi di masa lalu, dengan perubahan revolusioner yang dilakukan melalui pembersihan. Cara-cara lama dan baru tampaknya begitu mirip, menunjukkan alasan kuat soal dilakukannya proses-proses tersebut. Pembersihan-pembersihan demikian menunjukkan bahwa meskipun paradoksal, proses-proses ritual tradidional justru paling bisa mengekspresikan perubahan politik. Praktik transisional menunjukkan hasil pengamatan sosiologis tentang ritual sosial pemeliharaan dan reformasi: dengan cara-cara lama, pesan perubahan politik menjadi manifes,66 meskipun ia dibedakan dengan jaminan prosedural dan justifikasi liberal. Analisis terhadap bentuk-bentuk perubahan demikian menjelaskan bagaimana dalam masa transisi, ritual politik yang sudah ada tetap bisa memajukan tujuan untuk transformasi. Demiliterisasi terhadap Negara Kemanan Nasional Dengan tingkat kebertahanan pemerintahan otoriter yang tinggi, bagaimana cara bergeser dari rezim militer ke sistem yang lebih liberal? Mungkin tantangan terbesar bagi keadilan administratif adalah penggunaan tindakan administratif untuk mengubah negara keamanan nasional. Akhir Perang Dunia Kedua menimbulkan suatu dorongan untuk memelihara 65 Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, New York: Macmillan, 1968. Lihat Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Ithaca: Cornell University Press, 1966; Paul Connerton, How Societies Remember: Themes in the Social Sciences, Boston: Cambridge University Press, 1989. 66 26 perdamaian dan demokrasi. Tujuan untuk memelihara perdamaian ini mendorong sejumlah inisiatif, dari pendirian PBB dan komitmenya untuk memelihara perdamaian hingga demiliterisasi negara-negara yang kalah. Penyerahan tanpa syarat Jerman dan Jepang diterjemahkan sebagai penyerahan semua kekuasaan prospektif untuk berperang dalam konstitusi pasca-perang kedua negara tersebut.67 Di negara-negara yang dianggap berpotensi menyebarkan peperangan, batasan-batasan baru pasca-perang meredam kekuasaan militer. Meskipun terdapat dorongan untuk melakukan demiliterisasi, dengan adanya Perang Dingin, hal ini tidak bertahan lama. Ini terutama terjadi di Amerika Latin, di mana polarisasi dunia yang semakin menajam mempengaruhi belahan dunia ini, karena usaha untuk mempertahankan sistem ekonomi ala Barat berjalan bersama dengan penindasan, juga karena negara-negara kapitalis mendukung para diktator, selama mereka menolak komunisme. Pada dekade 1950-an, hampir setengah dari negara-negara di Amerika Latin berada di bawah pemerintahan militer. Dekade 1960-an dan 1970-an menunjukkan semakin naiknya kekuasaan militer, ketika negara-negara yang bahkan selama itu itu dikenal sebagai negara demokratik, seperti Cili, jatuh ke tangan militer. Pada awal dekade 1980-an, praktis seluruh benua tersebut dikuasai oleh pemerintahan militer yang represif.68 Inilah masa kejayaan negara keamanan nasional. Dengan militer yang kokoh di tampuk kekuasaan, politik kepartaian seperti biasa tidaklah cukup; pemilihan umum bukanlah jawaban. Bahkan bila militer secara resmi mengalihkan kekuasaan, suatu budaya penerimaan terhadap pemerintahan militer memungkinkan perimbangan kekuasaan secara de facto antara sipil dan militer, yang dicapai dengan kedok pemerintahan sipil. Di wilayah Amerika, transisi dari otoritarianisme berarti suatu perjuangan untuk menundukkan militer kepada pemerintahan sipil. Kegagalan politik partai mendorong respon struktural lainnya dalam masa transisi. Meskipun terdapat liberalisasi politik, hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban militer sebagai suatu organisasi.69 Namun, satu negara, Kosta Rika, menghapuskan sama sekali kekuatan militer dengan menghapus angkatan bersenjatanya.70 El Salvador pasca-perang saudara menunjukkan bentuk demiliterisasi yang lebih sederhana. Ketika kesepakatan damai yang ditengahi PBB mengakhiri perang saudara berdarah dan berkepanjangan di negara itu, terdapat seruan untuk memperbaiki secara besarbesaran aparat keamanan negara itu. Kesepakatan damai antara pemerintah El Salvador dan Frente Farabundo Marti para la Liberatión Nacional (FMLN) tergantung pada pembersihan militer dan polisi. FMLN sepakat untuk menyerahkan senjatanya dengan syarat “purifikasi” militer, jadi bahwa demobilisasi terhadap oposisi dipertukarkan dengan pembersihan aparat keamanan nasional. Dengan demiliterisasi dan penyerahan senjata, oposisi diizinkan masuk ke dalam lingkup politik dan bebas untuk membentuk partai politik sebagai imbalan dari pengucilan terhadap aparat keamanan nasional dari domain politik yang sah. Ada pertanyaan yang tersisa: bagaimana mengubah militer? Apa kaitan antara individu dengan militer sebagai sistem, terutama berkaitan dengan pelanggaran dan potensi peran 67 Bandingkan Konstitusi Jepang, Pasal 9 (membatasi organisasi militer Jepang hanya untuk kapasitas bela diri) dengan Basic Law Jerman, Pasal 115a. 68 Lihat Americas Watch, Report on Human Rights and U.S. Policy in Latin America, With Friends Like These, ed. Cynthia Brown, New York: Pantheon Books, 1985. 69 Untuk diskusi tentang bebrepa pergantian rezim di wilayah ini, lihat Guillermo O’Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. 70 Lihat Leonard Bird, Costa Rica: The Unarmed Democracy, London: Sheppard Press, 1984. 27 militer dalam transformasi demokratik? Transformasi angkatan bersenjata di El Salvador dilakukan dengan kombinasi perubahan sistemik dan pembersihan individual. Transformasi institusional terhadap aparat keamanan dilakukan dengan dua cara pembersihan: penyingkiran individu dan restrukturisasi organisasi kemiliteran. Pemecatan terhadap pelaku pelanggaran individual adalah satu cara untuk membersihkan militer, menghilangkan elemen-elemen nondemokratis dari badan ini.71 Dalam bahasa Spanyol, Purificación, atau purifikasi, berarti meneliti peran militer dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu penyelidikan untuk memastikan kemungkinan militer bersikap demokratis di masa depan.72 Meskipun rencana awalnya adalah perubahan cepat terhadap aparat militer, mendorong militer untuk mengalah kepada pemerintahan sipil adalah perjuangan yang panjang. Ketika komisi ad hoc mengidentifikasi individu-individu pelaku pelanggaran, daftar panjang para pelaku mencakup perwira-perwira tinggi, termasuk menteri pertahanan, yang terkait dengan pembunuhan para Yesuit yang terkenal. Lebih buruk lagi, di antara nama-nama yang diidentifikasi untuk dipecat terdapat nama-nama para perwira yang terlibat dalam perjanjian perdamaian. Perlawanan militer terhadap rencana pembersihan, dan ancaman kudeta, memperlambat pembersihan. Setengah tahun setelah jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, jajaran tertinggi angkatan bersenjata dibebastugaskan: pembersihan militer di El Salvador memiliki justifikasi penangkalan. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dianggap cenderung untuk mengulang kelakuannya, karena itu, harus disingkirkan dari posisi kekuasaan. Meskipun penyingkiran individual demikian berdasar pada justifikasi yang kuat, pada masa biasa, hal demikian hanya bisa dilakukan setelah adanya due process. Pada akhirnya, konflik antara kepentingan bersama dan hak due process individual ini ditengahi dengan kompromi, suatu pembersihan parsial yang menyingkirkan individu, tapi tidak memberikan stigma yang dikaitkan dengan peradilan pidana. Transformasi militer disyaratkan pada kaitan yang jelas dan erat antara individu dan organisasi, yang terkait erat dengan pemahaman masyarakat tentang militer sebagai institusi. Penggunaan tindakan transisional kolektif mengasumsikan kaitan erat antara individu yang terpengaruh dan kolektifnya. Dalam militer, terdapat kaitan erat seperti jelas dalam pemahaman tentang tanggung jawab pidana, yang dibicarakan dalam bab terdahulu tentang peradilan pidana. Dalam struktur militer, pemahaman tentang konstruksi “jaringan komando” menunjukkan tanggung jawab para pemimpin, pemikulan tanggung jawab yang lebih dari sekadar individu, namun juga berpengaruh pada bagian-bagian lain dari organisasi ini. Pergumulan tentang pembersihan militer El Salvador menunjukkan bagaimana pembersihan, meskipun konsekuensinya bersifat punitif, tidak melalui proses yang biasanya berjalan bersama penghukuman. Ini tampak jelas bahkan dalam apa yang bisa dikatakan sebagai pembersihan tahap pertama. Penerbitan daftar nama dalam lingkup publik, seperti lustrasi setelah komunisme, adalah pengutukan publik terhadap pelanggaran di masa lalu. Daftar nama mereka yang harus dibersihkan itu berkaitan erat dengan pembersihan tahap berikutnya; karenanya, melakukan pencopotan secara bertahap sehingga tidak lagi dikaitkan dengan daftar tersebut berarti mengurangi “hukuman” yang diterima. Begitu proses pembersihan dipisahkan dari daftar tersebut dan pencopotan dilakukan dengan alasan mutasi rutin dan pensiun, stigma hukuman berkurang drastis. Tanpa keputusan hukum, sanksi tidak 71 Lihat OED, entri “expurgate”. Lihat Lawyers Committee for Human Rights Report, El Salvador’s Negotiated Revolution: Prospects for Legal Reform, New York: Lawyers Committee for Human Rights, 1993, 50-56. 72 28 memiliki aspek punitif, dan hanya memberikan perubahan dalam status kemasyarakatan. Akomodasi ini mengurangi ketegangan yang timbul akibat pembersihan – dan menjaga perdamaian. Transformasi negara keamanan nasional juga berarti perubahan kepolisian, karena tidak saja militer, namun polisi juga terkait dalam pelanggaran di masa lalu. Polisi lama akan dibersihkan, dimobilisasi dan diganti oleh kepolisian yang dikendalikan oleh sipil, bukan dengan mengeluarkan elemen lama, namun dengan memaksa memasukkan elemen-elemen baru. Pembersihan (purge) dalam konteks ini menunjukkan arti lain, yaitu membersihkan satu cairan dengan memasukkan cairan lainnya.73 Transformasi polisi dilakukan dengan memasukkan sejumlah anggota baru sipil yang “bersih”. Transformasi terhadap organisasi ini memiliki arti bahwa sebagian besar anggotanya harus tidak terkait dengan perang saudara yang lewat. Pergantian personel dengan perbandingan 60:40 dilakukan untuk mengimbangkan kuota antara mantan pemberontak dan militer, agar transformasi politik dapat terlaksana. Lebih dari setengah anggota institusi harus terbebas dari noda masa lalu, sehingga ada dua kelompok seimbang yang tersisa: para anggota polisi lama yang telah disaring dan pasukan pemberontak yang telah didemobilisasi.74 Konstruksi transformasi politik setelah berakhirnya pemerintahan militer sebagian ditentukan oleh rezim yang digantikannya. Perubahan yang berarti haruslah bersifat kritis atau diskontinu dengan praktik-praktik di masa lalu. Jika tidak demikian, ia masih merupakan kelanjutan dari rezim lama. Terdapat konsepsi transisional yang cair tentang kaitan perubahan struktural dan individual. Transformasi institusional dalam hal ini berlangsung melalui gabungan perubahan struktural dan individual, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengimbangan antara faksi-faksi politik. Restrukturisasi aparat keamanan dengan menempatkan faksi-faksi politik yang berkekuatan sama, yaitu pendukung pemerintah dan mantan pasukan pemberontak, merupakan cara untuk mencegah repolitisasi, untuk mencegah dominasi satu pihak terhadap institusi. Ketakutan terhadap dominasi politik oleh satu faksi merupakan hal yang umum di Amerika, dan pencegahannya melalui seperangkat sistem pengawasan dan pengimbangan (melalui representasi politik luas) telah lama terjadi di wilayah ini.75 Jalan menuju transformasi politik memiliki banyak pilihan, dari individual ke kolektif, dengan penyingkiran individu-individu anggota militer yang melakukan pelanggaran, dan memasukkan anggota-anggota baru yang “bersih”. Dalam institusi militer, kaitan antara anggota individual dan militer sebagai badan amat erat, seperti tampak dalam struktur komandonya. Dengan demikian, demiliterisasi di Amerika mencakup baik individu maupun struktur, yang tercermin dalam pemahaman tentang tanggung jawab dalam struktur militer. Dengan demikian, transisi dari pemerintahan militer mentolerir ketidaktaatan pada due process individual, tidak seperti dalam intuisi kita tentang kedaulatan hukum dalam sistem demokrasi yang sudah mapan. Tentang Perang dan Damai 73 Lihat OED, entri “purge”. Lihat Americas Watch, El Salvador and Human Rights: The Challenge of Reform, New York: Human Rights Watch, 1991. 75 Untuk pengetahuan awal argumen ini, lihat James Madison, The Federalist No. 10, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1961. 74 29 Usaha-usaha untuk mereformasi aparat keamanan nasional sering kali dirasionalisasikan melalui perdamaian. Pembersihan sering kali dijadikan bagian dalam kesepakatan damai, bila perubahan politik dijustifikasi dengan alasan perdamaian dan rekonsiliasi. Justifikasi perdamaian ini misalnya terdapat di dalam alasan untuk melakukan pembersihan di El Salvador. Menurut kesepakatan damai, demobilisasi militer akan memajukkan negara tersebut ke tahap selanjutnya. Pembersihan aparat keamanan dilangsungkan berdampingan dengan doktrin keamanan yang baru, yang menundukkan militer pada konstitusi.76 Pembersihan di El Salvador ini memajukkan kepentingan perdamaian, karena ia menjadi bagian dari kesepakatan damai. Lebih lanjut lagi, usaha untuk memajukan tanggung jawab individual menghapuskan dosa kolektif dari militer secara institusional, dan memberikan legitimasi baru bagi militer. Rekonstruksi militer lain di wilayah ini juga dilakukan dengan alasan perdamaian. Kaitan antara transformasi, keamanan dan perdamaian juga terlihat di Haiti. Setelah berakhirnya puluhan tahun masa pemerintahan militer dan ditariknya pasukan multinasional, timbul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan aparat keamanan Haiti. Pasukan polisi sementara yang masih tersusun dari bekas anggota militer yang represif, bahkan belum melalui proses penyaringan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.77 Ketiadaan usaha untuk menyingkirkan para pelanggar, dan pemindahan personel dari satu bagian aparatur militer ke bagian lainnya hanya mendorong persepsi tentang ketiadaan otoritas dan legitimasi dalam badan tersebut.78 Ketiadaan badan pelaksana hukum yang sah ini menandakan ketiadaan keamanan dan perdamaian. Kesepakatan serupa juga dilakukan di Kamboja, yang memberikan kekuasaan kepada Otoritas Transisional PBB di Kamboja (UNTAC) untuk membuat keputusan tentang personel. Meskipun pembersihan transisional umumnya kontroversial, namun pembersihan terhadap aparat keamanan mendapat dukungan luas.79 Transformasi terhadap sektor keamanan menjustifikasi tindakan-tindakan yang radikal, karena di sini kaitan antara pembersihan sebagai suatu cara dan tujuan kedaulatan hukum prospektif tampak paling jelas. Bila ancaman terhadap keamanan terletak dalam satu sektor tersendiri, yaitu aparat keamanan, transformasi politik bergantung kepada restrukturisasi dan penciptaan legitimasi bagi sektor tersebut. Sebaliknya, bila perubahan demikian tidak dilakukan, pasukan keamanan akan dianggap tidak mampu menjamin keamanan. Praktik transisional berkaitan sektor keamanan menunjukkan kaitan erat antara perubahan struktural dan transformasi ke sistem kedaulatan hukum di bawah pemerintahan sipil. Pembersihan aparat keamanan memperlihatkan hubungan dekat antara individu dengan kolektif dalam lingkup-lingkup tertentu, dan menunjukkan justifikasi penggunaan cara-cara tersebut untuk melaksanakan transformasi politik dari sistem negara keamanan nasional. Bahkan, dengan dasar pada keamanan, pembersihan pasca-militer merupakan cara terbaik untuk melakukan transformasi politik. Bahkan dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, pembersihan politik sering kali didasarkan atas alasan keamanan nasional dan perdamaian, terutama di masa perang. Sebagai contoh, pada masa 76 Lihat Kesepakatan Damai, Lampiran Surat PBB tertanggal 27 Januari 1992 dari Wakil Permanen El Salvador untuk PBB, dialamatkan kepada sekretaris jenderal, A/ 46/864 S/23501 (30 Januari 1992): 2-3. 77 Lihat Human Rights Watch/Americas National Coalition for Haitian Refugees, Security Compromised: Recycled Haitian Soldiers on the Front Line, Vol. 7, No. 3, New York: Human Rights Watch, 1995. 78 Ibid., 1-2, 67. 79 Bahkan oleh komunitas hak asasi manusia. Lihat misalnya Human Rights Watch World Report 1996, New York: Human Rights Watch, 1997, 91-93. 30 Perang Dunia Kedua, penahanan massal terhadap warga negara Amerika Serikat atas dasar kelompok etnik dijustifikasikan atas alasan “keamanan nasional”.80 Dasar untuk tindakan penahanan berbasis etnik ini kemudian dijadikan alasan untuk melakukan pengucilan politik. Pengucilan politik serupa mendapatkan justifikasi yang sama dalam masa Perang Dingin. Sementara alasan keamanan dalam kondisi biasa tidak dapat diterima, pada saat perang dan transisi radikal, alasan ini menjadi kuat. Pembersihan pasca-militer tetap merupakan tindakan transisional yang luar biasa, yang merupakan respon terhadap persepsi tertentu terhadap sumber-sumber kelemahan institusional, yang bersifat kritis, karena demiliterisasi harus menjelaskan kaitan antara keamanan dan legitimasi serta otoritas. Bila aparat keamanan tidak tunduk pada hukum, timbul ancaman dari institusi yang sebenarnya bertugas untuk melindunginya, yang malah berpeluang melakukan represi dan mengganggu keamanan. Perdebatan tentang pembersihan militer dalam transisi menunjukkan masalah besar tentang kedaulatan hukum yang dihadapi di wilayah ini. Pembersihan militer menunjukkan kesukaran dalam usaha mereformasi institusi penegakan hukum yang terpolitisasi, dan menunjukkan batas-batas kemampuan keadilan administratif. Namun, bagi rezim-rezim yang baru bergeser dari pemerintahan militeristis, demiliterisasi memunculkan batasan baru bagi kekuasaan militer, dan menunjukkan kemenangan pemerintahan sipil; sehingga demiliterisasi dipandang bisa menawarkan satu jalan untuk mengembalikan kedaulatan hukum. Demokrasi Militan Dalam transisi kontemporer sejak akhir Perang Dunia Kedua, hukum publik memberikan perlindungan kepada kejahatan di masa lalu dalam bentuk yang sering kali disebut sebagai “demokrasi militan”.81 Demokrasi militan adalah suatu respon transisional yang mencoba menjawab paradoks represi modern, yang sering kali berakar pada demokrasi, karena kekuasaan diperoleh sebagai hasil pemilihan umum secara bebas. Bila pemerintahan represif tampil sebagai akibat dari proses demokrasi, bagaimana kejahatan ini disikapi: sejauh mana kesalahan rakyat, partai dan negara? Dan ke mana transformasi akan diarahkan? Setelah berakhirnya penderitaan akibat fasisme, ini menjadi pertanyaan sentral dalam keadilan transisional. Nazisme menancapkan kukunya di Jerman melalui politik parlementer biasa, dengan mayoritas politik yang berhasil menentang tatanan politik yang ada.82 Fasisme dan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkannya dianggap tumbuh dari kelemahan Republik Weimar dan partai-partai politik ekstremis yang menjadi gerakan populis yang meruntuhkan demokrasi. Dengan peninggalan sejarah kegagalan demokrasi ini setelah keruntuhan Nazi, timbul pertanyaan tentang bagaimana melindungi demokrasi di masa depan. Di sini, ancaman terbesar bagi liberalisme adalah partai-partai yang bekerja dalam sistem politik demokratis untuk meruntuhkannya. Peninggalan sejarah represi politik inilah yang mendorong respon 80 Lihat Korematsu v. United States, 323 US 214 (1944). Lihat Dennis v. United States, 241 US 494 (1951) (menyetujui penindasan atas dasar Smith Act terhadap para pimpinan nasional partai komunis Amerika Serikat). 82 Lihat Hans Mommsen, From Weimar to Auschwitz, Princeton, N.J: Princeton University Press, 1991. Lihat umumnya Robert Moss, The Collapse of Democracy, London: Abcus, 1977. 81 31 yang dikenal sebagai “demokrasi militan” – usaha untuk melindungi sistem demokratis dari ancaman internal. “Demokrasi militan” merespon tirani masa lalu tertentu, yang karena itu ia juga bermakna mendefinisikan ulang demokrasi. Demokrasi militan menjustifikasi peredaman berdasarkan konstitusi terhadap partai-partai politik yang bila dibiarkan begitu saja dapat mengancam tatanan demokratis; dalam skema demokrasi militan, partai-partai “inkonstitusional” akan disingkirkan dari perpolitikan yang sah.83 Penyingkiran terhadap kelompok-kelompok politik tertentu akan menyusun batasan baru terhadap sistem politik. Dilema yang ditimbulkan demokrasi militan adalah pembatasan demokrasi atas nama demokrasi. Ini adalah satu bentuk ekstrem dari persyaratan dan pelucutan politik yang telah dibicarakan. Hingga titik tertentu, skema ini menjadi lemah karena proses-prosesnya: meskipun pelarangan partai bisa dilakukan oleh cabang-cabang politik, ia hanya diputuskan oleh sikap pengadilan konstitusional. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai “antidemokrasi” dan di luar konstitusi adalah suatu masalah penafsiran konstitusi. Jadi, dalam interpretasinya terhadap demokrasi militan, pengadilan konstitusional berperan sebagai pelindung tatanan demokrasi yang baru. Tepat setelah berakhirnya perang, dalam kasus Partai Sosialis, hanya terdapat satu masalah: sejauh mana ia terkait dengan partai Nazi, sehingga partai tersebut harus disingkirkan. Partai neo-Nazi ini merupakan paradigma partai antidemokrasi, karena keanggotaan, struktur dan ideologinya tidak lain adalah kelanjutan dari partai Nazi yang lama.84 Namun, dengan adanya Perang Dingin di Eropa, ancaman potensial terhadap demokrasi tidak sekadar neo-nazisme. Ketika pemerintah Konrad Adenauer mengesahkan Pasal 21, yaitu tindakan konstitusional untuk melarang Partai Komunis Jerman, pertanyaan yang relevan menurut pengadilan adalah apakah partai tersebut berusaha untuk merusak tatanan “demokratis”. Harus ada bukti “bahaya nyata” yang diterapkan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam meninjau perundang-undangan serupa untuk melarang partai komunis di Amerika Serikat pada masa perang dingin. Tindakan keras terhadap sistem demokrasi kepartaian tampaknya salah. Namun menurut pandangan Pengadilan Konstitusional Jerman, hal tersebut dijustifikasikan oleh pengalaman sejarah dan penindasan yang dialami negara itu. Penindasan secara konstitusional terhadap satu partai hanya dilakukan dua kali dalam masa tujuh tahun pertama terbentuknya pemerintah baru pada tahun 1949, dengan pelarangan partai neo-Nazi pada tahun 1952 dan partai komunis pada tahun 1956.85 Seiring perjalanan waktu, kebutuhan untuk merasakan bahaya yang berlebihan seperti itu menjadi berkurang. Pada tahun 1968, ketika Partai Komunis Jerman muncul kembali, representasi politik demikian tidak lagi dianggap kontroversial. Baik di Jerman maupun di Amerika Serikat, penindasan terhadap partai komunis hanya dilakukan selama periode tertentu setelah berakhirnya perang; ketika prinsip demokrasi militan sedang dipegang teguh. 83 Untuk asal usul istilah “demokrasi militan” dalam teori politik, lihat Karl Lowenstein, “Militant Democracy and Fundamental Rights”, American Political Science Review 31 (1937): 417. Untuk provisi konstitusional yang mendefinisikan lingkup keterancaman demokrasi konstitusional, Basic Law, Pasal 21(2) menyatakan: “Partaipartai yang karena tujuannya atau karena perilaku pengikutnya berusaha melemahkan atau menghapuskan tatanan mendasar demokratis dan kebebasan atau mengancam keberadaan Republik Federal Jerman akan dianggap inkonstitusional”. 84 Lihat Socialist Reich Party case, 2 BverfGE 1 (Jerman, 1952) dan Communist Party Case, 5 BVerfGE 85 (Jerman, 1956). 85 Ibid. 32 Penindasan konstitusional terhadap sebuah partai jarang dilakukan di Jerman, dan pada praktiknya hal tersebut pun dibatasi pada masa transisional. Namun, di seluruh wilayah tersebut, dalam perubahan sistem konstitusional Eropa pasca-perang, respon terhadap totalitarianisme sering kali mengambil bentuk demokrasi militan. Demokrasi dijadikan batasan konstitusional terhadap perkumpulan politik. Misalnya, konstitusi Turki menyatakan bahwa “partai politik harus sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi”. Konstitusi Portugal membatasi kebebasan berkumpul berdasarkan kondisi pasca-perang, dengan melarang “organisasi yang memiliki ideologi fasis”.86 Di seluruh wilayah ini, respon terhadap ketakutan sejarah atas sistem politik demokratis yang disalahgunakan mengambil bentuk represi konstitusional. Melalui respon struktural ini, bentuk-bentuk ekspresi politik yang berbahaya ditempatkan di luar tatanan politik yang ada. Pembatasan terhadap bentuk perpolitikan yang legal beralih menjadi kedaulatan hukum dalam masa transisi, kendatipun pelaksanannya dengan standar konstitusional transisional ini memberikan kontribusi lebih besar terhadap identitas politik negara itu. Respon pasca-perang terhadap fasisme adalah menyingkirkan oposisi non-demokratik di luar sistem politik yang legal. Demokrasi militan memunculkan dilema tentang apa yang yang harus dilakukan terhadap partai politik yang membahayakan demokrasi yang memungkinkan terbentuknya. Kasus transisional ini menjelaskan patologi lebih luas dalam politik demokratis: pemerintahan tidak liberal yang muncul sebagai akibat dari penggunaan cara-cara demokratis. Kasus ini menunjukkan bagaimana demokrasi menimbulkan dilema cara-tujuan yang dibicarakan dalam bab ini. Demokrasi militan menunjukkan ketegangan ini dan menunjukkan bahwa paling tidak dalam masa transisi, proses-proses non-liberal bisa ditolerir, bila ditujukan untuk membangun demokrasi. Partai dan Rakyat Mungkin usaha paling radikal yang dilakukan sebuah partai untuk melakukan transformasi politik tampak dalam transisi pasca-komunis kontemporer. Pada saat kejatuhan Uni Soviet, pembersihan diri oleh Partai Komunis merupakan tanda terjelas dari perubahan politik. Keruntuhan ini dimulai pada tahun 1991, ketika Presiden Mikhail Gorbachev menyerukan kepada komisi Sentral Partai Komunis Uni Soviet untuk membubarkan diri. Di berbagai republik anggota Uni Soviet, partai-partai komunis bubar, entah sebagai akibat pelarangan, dekrit presiden, atau reformasi konstitusional. Berakhirnya sistem satu partai, sekaligus penghapusan privilesenya, menandakan awal tatanan politik baru yang lebih terbuka. Karena status partai sebelumnya dimapankan dalam skema hukum, keruntuhannya pun diformalkan melalui hukum. Transformasi politik hanya bisa dilakukan dengan memutuskan kaitan antara kekuasaan partai dan negara, sehingga kedaulatan dapat dipindahkan dari partai ke rakyat.87 Melalui perubahan konstitusional, partai komunis dipisahkan dari aset-asetnya, dan dilarang untuk menerapkan kekuasaannya.88 Bahkan istilah Marxisme-Leninisme dihilangkan dari 86 Konstitusi Republik Turki, pasal 69 (amendemen 1995); Konstitusi Portugal, pasal 46 (1992). Lihat misalnya Konstitusi Republik Bulgaria, 12 Juli 1991, Konstitusi Republik Hongaria, setelah diamendemen Akta No. 31, 1989, pasal 3(3). 88 Lihat Gordon Wightman (ed.), Party Formation in East-Central Europe: Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria, Adershot, Inggris: Edward Elgar, 1995, 205. 87 33 konstitusi. Dengan kehilangan legitimasi dan dipenuhi korupsi, rezim tersebut runtuh dengan sendirinya. Setelah terjadinya perubahan politik kritis, timbul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Partai Komunis? Apakah partai tersebut, yang terbiasa dengan sistem partai tunggal, dapat beradaptasi ke sistem kepartaian yang demokratis? Apakah institusi ini dapat melemahkan konsolidasi tatanan demokratis yang liberal? Sejauh mana partai komunis dapat diperlakukan setara dengan partai-partai politik lainnya dan diizinkan bersaing dalam perebutan kekuasaan? Setelah pemerintahan partai tunggalnya yang represif, apakah partai komunis masih memiliki legitimasi? Atau apakah identitas partai tersebut pada dasarnya sinonim dengan negara totaliter? Dalam pandangan terakhir ini, adanya perubahan berarti menuntut pembubaran partai tersebut. Sementara bila identitas partai tidak disamakan dengan negara, ia tetap bisa berperan dalam transisi ke sistem politik yang lebih demokratis. Pertanyaan ini adalah pertanyaan kunci, dengan dampak potensial di seluruh wilayah ini. Isu ini menjadi signifikan pada tahun 1991, ketika Pengadilan Konstitusional Rusia yang baru dibentuk menegaskan konstitusionalitas partai komunis. Pada bulan Agustus 1991, segera setelah berakhirnya usaha kudeta, Presiden Boris Yeltsin menyatakan Partai Komunis Rusia sebagai tidak konstitusional melalui keputusan presiden, yang diikuti dengan pembubaran aparat kepemimpinan partai itu, politbiro dan Komite Sentral, bersama-sama dengan struktur lokal partai.89 Namun Rusia tidak seperti Jerman, tidak memiliki skema konstitusional untuk merepresi partai-partai ekstremis. Akibatnya, terdapat bebarapa isu yang diajukan ke pengadilan: konstitusionalitas Partai Komunis Uni Soviet, dan juga konstitusionalitas keputusan eksekutif yang melarang partai tersebut atas dasar konstitusi.90 Baru setelah para aktor politik menggunakan Pengadilan Konstitusional untuk membatalkan larangan Yeltsin tersebut, Parlemen buru-buru mengubah konstitusi untuk memungkinkan tinjauan Mahkamah Agung terhadap konstitusionalitas partai politik.91 Represi konstitusional terhadap partai politik model Jerman menyatakan bahwa Pengadilan Konstitusional adalah aktor utama yang memutuskan apakah suatu perilaku dianggap “tidak demokratis”. Namun di Rusia pasca-Soviet, apa arti tinjauan konstitusional terhadap partai? Pertanyaan yang timbul adalah apakah usaha larangan Yeltsin tersebut didasarkan pada kemungkinan abstrak subversi, ataukah “tindakan presiden tersebut disebabkan oleh kebutuhan objektif untuk mencegah munculnya upaya untuk kembali ke situasi terdahulu”.92 Dilakukan segera setelah usaha kudeta yang gagal, keputusan Yeltsin menimbulkan pertanyaan tentang kesalahan partai. Dengan menuduh bahwa pimpinan partai bertanggungjawab atas usaha kudeta tersebut, keputusan Yeltsin menyatakan, “Jelas bahwa selama struktur partai komunis tetap bertahan, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi kudeta lain.”93 Dalam proses hukum tentang pelarangan partai ini, para saksi memberikan kesaksiannya tentang setengah abad korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai, pengungkapan pelanggaran di Katyn dan Afghanistan, dan menuduh bahwa kepemimpinan tingkat tinggi 89 Kutipan dari Keputusan Presiden Federasi Rusia, 23 Agustus 1991, No. 25, “Tentang Pelarangan Kegiatan Partai Komunis Uni Soviet” (arsip University of Chicago Center for Constitutionalism in Eastern Europe). 90 Lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30 November 1992, hlm. 104. 91 Lihat Konstitusi Federasi Rusia, Pasal 165-1, menyatakan bahwa “Pengadilan Konstitusional Federasi Rusia memutuskan konstitusionalitas ... partai-partai politik dan organisasi publik lainnya”. 92 Communist Party Decision (arsip University of Chicago Center for Constitutionalism in Eastern Europe). 93 L. Aleksandrova, “Decree of the RSFSR President on the Activities of the CPU and CP RSFSR”, Rossiiskaya Gazeta, 9 November 1991, tersedia di Lexis, World Library, arsip SPD. 34 partai bertanggung-jawab. Setelah puluhan tahun penindasan, sifat partai yang mengancam ini menjadi jelas. Dalam kondisi baru saja terlepas dari sistem totaliter yang represif, di mana partai tidak tunduk pada kedaulatan hukum, timbul pertanyaan tentang bagaimana mentransformasi kekuasaan partai dan menciptakan sistem multi partai yang stabil. Penindasan konstitusional terhadap partai memberikan sebagian tanggung jawab kepada pengadilan yang independen. Dalam mempertimbangankan pelarangan partai di Rusia, Pengadilan Konstitusional akhirnya memberikan keputusan yang adil bahwa justifikasi demokrasi memungkinkan pelarangan partai pada tingkat eselon tinggi, yaitu Politbiro dan Komite Sentral, namun tidak demikian pada tingkat lokal. Melalui proses yudisial yang membahas bagaimana satu partai dianggap melakukan pelanggaran, justifikasi terhadap tindakan negara ini bisa diumumkan. Pengadilan Konstitusional memainkan peran penting dalam proses kedaulatan hukum minimal yang merasionalkan hal yang sebenarnya bisa dianggap sebagai pembersihan politik. Demokrasi Militan dan Negara Liberal Pertimbangkanlah penindasan konstitusional terhadap sebuah partai dan prinsip dasar demokrasi militan. Dalam contoh-contoh di atas, partai-partai politik tertentu dikekang karena dianggap sebagai ancaman terhadap liberalisasi. Ancaman ini bersifat kolektif, demikian pula sanksinya – pembubaran partai dan penyitaan propertinya. Pemberian sanksi kepada partai politik mengekspresikan keputusan politik atas dasar politik, yang tampak tidak sesuai dengan intuisi kita tentang sistem bekerjanya negara liberal. Maka, timbullah pertanyaan: apakah tindakan ini adalah benar-benar usaha perlindungan, yang bisa dijustifikasi, dari ancaman konkret terhadap tatanan konstitusional? Atau semata-mata pembatasan yang dipolitisasi terhadap minoritas politik yang tidak disukai? Sebagai titik awal, bila suatu mayoritas politik membatasi minoritas untuk berpartisipasi dalam lingkup publik, kebijakan ini pasti akan dicurigai. Namun, apakah hal sebaliknya merupakan skenario yang mungkin akan bergantung pada peran pengadilan. Demokrasi militan adalah respon transisional yang berpremis pada pandangan tertentu tentang patologi politik demokratis: paradoks demokrasi dan pemerintahan yang tidak liberal. Demokrasi militan menunjukkan ketegangan yang inheren dalam demokrasi dan liberalisme, terutama dalam demokrasi konstitusional. Sejauh mana dilema demokrasi ini dapat digeneralisasikan? Dalam gelombang transisi dan konstitusionalisme kontemporer, timbul pertanyaan tentang bagaimana merespon pemerintah yang tidak liberal dan apakah perlu mengikuti langkah konstitusional Jerman. Sejauh mana respon demokrasi militan ditiru dan menjadi panduan bagi transformasi politik partai di wilayah lainnya? Pertanyaan ini timbul dalam transisi pasca-komunis. Demokrasi militan merupakan respon terhadap tirani yang terkait erat dengan sejarah Eropa. Di Eropa Timur dan Rusia, pemerintahan represif timbul bukan dalam perpolitikan model Weimar, namun dari totalitarianisme. Di wilayah ini, sejarah patologi politik bukan disebabkan karena terlalu banyaknya demokrasi, misalnya karena pengambilalihan kekuasaan oleh partai-partai pinggiran, namun oleh hal sebaliknya – pemerintahan partai tunggal. Namun, argumen untuk memperluas pandangan demokrasi militan adalah bahwa bila pemerintahan represif timbul dari proses yang jelas-jelas tidak demokratis, pemerintahan partai tunggal demikian biasanya mempertahankan kekuasaannya dalam waktu lama hanya bila masyarakat menaatinya. Namun 35 skema demokrasi militan, dalam ketiadaan tradisi demokrasi yang kuat, dapat mengancam demokrasi yang baru tumbuh. Bila kekuasaan konstitusional untuk menindas demikian tidak dibatasi, selain melalui interpretasi yudisial, sistem demokrasi tidak akan bertahan lama. Fenomena keterancaman transisional ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas, tentang apakah dan sejauh mana, sistem demokrasi perlu memberikan panduan normatif terhadap sistem politik pada dasar yang lebih permanen. Model pasca-perang yang diterapkan di Jerman bergantung pada badan peradilan untuk bisa bekerja. Interpretasi yudisial mencerminkan usaha untuk bergeser dari tuduhan kabur tentang “ekstremisme politik”, ke alasan yang lebih objektif, seperti kekerasan politik. Jurisprudensi konstitusional modern mencerminkan interpretasi ini. Meskipun standar konstitusional tentang pelarangan partai cenderung bergeser ke arah yang lebih liberal, melindungi kebebasan berserikat dan berekspresi, selalu terdapat bahaya politisasi sistem peradilan. Bahkan dalam sistem demokrasi yang mapan, terdapat masa-masa ketika pengadilan tinggi suatu negara cenderung rentan terhadap politisasi, seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Pertanyaan transisional yang ditimbulkan oleh kerangka demokrasi bersyarat ini juga timbul dalam pertanyaan serupa tentang penggunaan cara-cara serupa dalam negara liberal. Misalnya, contoh kontemporer pelarangan partai di Eropa dan Timur Tengah, seperti di Aljazair dan Turki, mengambil alasan ekstremisme dan faksionalisme religius.94 Di seluruh Eropa, selalu terdapat partai-partai politik yang menyebut dirinya religius, sehingga timbul pertanyaan: di mana menarik batasnya? Bagaimana menyikapi partai-partai demikian dalam negara liberal? Dalam gelombang kontemporer transisi pasca-komunis, pertanyaan ini memiliki signifikansi besar. Politik identitas memberikan tantangan yang berat kepada negara yang sedang melakukan transisi, dengan konflik di Yugoslavia sebagai gambarannya yang terburuk. Namun, keadilan transisional menawarkan cara untuk merekonstruksi negara, tidak melalui politik identitas, namun melalui identitas politis dan juridis yang berdasarkan pada hak. Dilema transisional ini, meskipun terlihat dalam masa-masa luar biasa, menunjukkan ketegangan laten dalam teori demokrasi, yaitu potensi pertentangan antara proses dan tujuan demokratis. Konflik potensial ini sering tampak dalam pertanyaan tentang batasan toleransi dalam negara liberal.95 Sebagai contoh, dalam The Law of the Peoples, John Rawls menentang pendekatan “toleransi” kepada ancaman-ancaman politis terhadap demokrasi.96 Namun, ingatlah kembali dilema yang dibahas di bagian muka bab ini, tentang ketegangan dalam masa transisional, ketika dalam masa pergeseran dari represi di masa lalu, konstruksi demokrasi membutuhkan justifikasi untuk membatasi proses kaum mayoritas dan melakukan kompromi terhadap pandangan ideal tentang kedaulatan hukum. Ketegangan ini dirasionalkan dalam skema konstitusional yang didefinisikan oleh demokrasi militan, karena partai ekstremis harus ditekan, atau ia akan mengancam tatanan politik. Dalam pandangan ini, hanya penindasan 94 Lihat Kelly Couturier, “Turkey Bans Islam-Based Political Party”, Washington Post, 17 Januari 1998, hlm. A20. Tentang pembubaran Partai “Kesejahteraan”, lihat http://www.turkey.org/turkey/politics/p-party.htm. 95 Lihat Michael Walzer, On Toleration, New Haven: Yale University Press, 1997. Untuk pembicaraan terkait tentang agama. lihat Ruti Teitel, “A Critique on Religion as Politics in the Public Sphere”, Cornell Law Review 78 (1993): 747. 96 Lihat John Rawls, “The Law of Peoples”, dalam Stephen Shute dan Susan Hurley (eds.), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, 1993, New York: Basic Books, 1993. Lihat juga Yael Tamir, Liberal Nationalism, Priceton: Princeton University Press, 1993. 36 yang konstitusional memungkinkan rezim transisional untuk merekonstruksi identitas politiknya. Aspek politis dari tindakan-tindakan ini dapat dikurangi dengan adanya tinjauan yudisial. Garis yang direkonstruksi di sini adalah pada sifat transformasi yang “kritis”, karena ia menyangkut peran politik dan redefinisinya berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Bila tindakan administratif transisional dilakukan melalui proses konstitusional, bukan hanya politis, ia mendapatkan justifikasi dari demokrasi. Meskipun pada masa biasa, masalah dan peran tindakan-tindakan demikian sering kali disingkirkan ke latar belakang, namun ia memberikan definisi batasan keanggotaan dan partisipasi dalam lingkup politik secara konstitusional; dalam masa transisi, proses-proses tersebut berada di muka. Keadilan antar-Generasi Praktik-praktik yang dibicarakan di sini, dikaitkan dengan perubahan politik radikal, yang membentuk pemahaman masyarakat tentang transformasi politik. Praktik-praktik tersebut mendefinisikan “waktu politik”, yaitu periodesasi politik “sebelum” dan “sesudah”, berkaitan dengan masa lalu yang represif dan masa depan yang demokratis. Apa peran waktu dalam transformasi politik? Suatu kisah dalam Kitab Suci menunjukkan peran waktu dalam transformasi politik. Dalam eksodus orang-orang Israel dari Mesir, terdapat kisah tentang pergerakan suatu bangsa – menuju kebebasan. Dalam kisah biblikal ini, orang-orang Israel menghabiskan waktu empat puluh tahun di padang gurun, sebelum mereka dapat berpindah dari perbudakan di Mesir ke kehidupan yang baru sebagai orang bebas. Transformasi ini membutuhkan waktu empat puluh tahun. 22] Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suara-Ku, 23] pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka! Semua yang menista Aku ini tidak akan melihatnya ... 29] Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur dua puluh tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepada-Ku. 30] Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kujanjikan akan Kuberi untuk kamu diami ... 31] Tentang anakanakmu yang telah kamu katakan: mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan Kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. ... 33] dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan.97 Apa signifikansi empat puluh tahun di padang gurun ini? Dalam paradigma biblikal ini, transformasi dari orang-orang yang diperbudak menjadi orang-orang bebas membutuhkan waktu – tampaknya sekitar dua generasi. Transformasi ini tampaknya membutuhkan suatu tahapan transisional yang ditunjukkan oleh masa mereka berada di padang gurun. “Transformasi secara mendadak dari satu kutub ke kutub lainnya tidaklah mungkin”.98 Dampak pembersihan oleh waktu ini terasa oleh satu generasi, universal dan absolut. Tidak 97 Plaut (ed.), “Exodus”, dalam The Torah 18:22-23. Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, terjemahan Shlomo Pines, Chicago: University of Chicago Press, 1969, 54. 98 37 seorang pun yang mengalami perbudakan di Mesir akan mencapai Tanah Terjanji, bahkan Musa, pemimpin pembebasan meninggal sebelum bangsanya memasuki tanah baru, sehingga tersingkir dari partisipasi dalam kebebasan politik yang baru. Perjalanan waktu mendefinisikan generasi politik yang membentuk negara yang baru.99 Satu ilustrasi lain tentang peran waktu dalam mendefinisikan tahap-tahap dan generasi transformasi politik terlihat dalam pergeseran dari monarki ke republik. Syarat yang mencakup jangka waktu satu generasi menjadi dasar perubahan yang signifikan. Dalam Konstitusi Amerika tahun 1787, terdapat persyaratan kepemimpinan politik dalam mendefinisikan generasi yang boleh berpartisipasi. Pasal II Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa calon presiden harus memiliki kewarganegaraan “natural” dan berusia minimum tiga puluh lima tahun.100 Kedua syarat konstitusional ini, usia dan kewarganegaraan, dipilih untuk menyingkirkan para simpatisan monarki atau anak-anak mereka. Kedua syarat ini mengkonstruksikan generasi politik yang boleh berpartisipasi. Aturan ini mencegah orangorang yang dianggap mungkin tidak memiliki komitmen sepenuhnya terhadap kemerdekaan negara ini dan transisinya ke sistem republik, untuk memegang jabatan politik tertinggi. Meskipun persyaratan ini diciptakan pada masa perubahan politik substansial, mereka tetap menjadi parameter konstitusional untuk jabatan politik tertinggi ini hingga kini. Satu contoh lain dapat ditemukan dalam transisi kontemporer dari pemerintahan komunis di Eropa Timur, ketika “sebelum” dan “sesudah” ditentukan oleh pelucutan berdasarkan usia, untuk mentransformasi partai-partai politik dalam pergeseran menuju sistem multipartai. Di Hongaria, partai “Fidesz” yang didirikan setelah revolusi, memiliki arti harfiah sebagai “uni pemuda demokrat”, yang juga bisa diartikan sebagai “kepercayaan”. Dengan klaimnya bahwa ia bisa dipercaya dalam masa transisi tersebut, Fidesz memiliki aturan yang melarang orang berusia lebih dari tiga puluh lima tahun menjadi anggotanya. Syarat usia ini melambangkan keanggotaan yang bersih, terbebas dari kolaborator dan dianggap menjamin kepercayaan. Syarat ini baru dicabut lima tahun setelah terjadinya perubahan politik. Syaratsyarat berdasarkan waktu juga terlihat dalam politik pembalasan, ketika para mantan komunis kembali memegang kekuasaan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Bulgaria, ketika kaum sosialis kembali berkuasa, disahkanlah perundang-undangan yang mensyaratkan pengalaman lima tahun untuk memegang jabatan publik.101 Syarat pengalaman ini menyelubungi syarat sesungguhnya, yaitu ideologi yang mendukung komunisme, karena hanya mereka yang mendukung rezim terdahulu memiliki hal yang disyaratkan. Jadi, kualifikasi berdasarkan waktu bisa menjadi pengganti pelucutan politik secara terbuka. Syarat-syarat partisipasi dan representasi politik sering kali didasarkan pada waktu, bahkan pada masa-masa biasa. Bahkan, contoh sederhana adalah hak untuk memilih, yang bersyarat pada kewarganegaraan lebih dari lima tahun. Masa lima tahun ini sering kali dianggap perlu untuk menunjukkan loyalitas dan afiliasi politik, dan partisipasi. Selain kewarganegaraan, yang menjadi syarat keanggotaan dalam ranah politik, diperlukan syaratsyarat lain untuk posisi lain dalam representasi politik. Ritus purifikasi politik transisional adalah bentuk-bentuk ekstrem dari ritual serupa seperti sensus yang mendefinisikan komunitas 99 Plaut (ed.), “Exodus”, dalam The Torah 18: 22-23. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, pasal 11. Lihat juga Alexander Hamilton, The Federalist No. 69, ed. Jacob E. Cooke, Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1961 (menunjukkan perbedaan antara calon eksekutif dan raja Inggris). 101 Lihat Philippa Fletcher, “Bulgaria: Ex-Communist Win Control over Bulgarian Judiciary”, Reuter News Service, 15 Juli 1994, Lexis, arsip Bulgaria. 100 38 politik. Secara historis (sejak masa Romawi), hingga masa kini, dalam masa biasa, penghitungan warga negara biasanya dilakukan setiap lima tahun.102 Sensus ini merupakan bentuk lustrasi politik yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan parameter komunitas politik. Pelucutan berdasarkan waktu bisa berpengaruh luas, dan dampak pengucilan ini bersifat radikal, karena ia bisa menyingkirkan satu generasi politik. Namun, karena penyingkiran ini tidak secara eksplisit didasarkan pada ideologi, diskualifikasi berdasarkan waktu tampak netral secara politis dan tidak normatif. Syarat berdasarkan waktu ini sering kali tersembunyi, namun tersebar luas. Persyaratan demikian bisa mencegah semua anggota satu generasi politik, baik terpengaruh atau tidak oleh rezim yang lama, dari partisipasi dalam tatanan politik yang baru. Dengan cara ini, kualifikasi berdasarkan waktu menjadi selubung bagi diskualifikasi politik. Meskipun memiliki tampilan luar yang netral secara politik, ia bisa menimbulkan perubahan politik yang luar biasa. Melalui persyaratan ini, transformasi masyarakat dapat terlaksana seiring perjalanan waktu. Identitas politik negara terbentuk bersama jalannya waktu. Bila syarat berdasarkan usia atau waktu diberlakukan dalam partisipasi politik, satu generasi menanggung beban transformasi politik. Generasi transisional ini diminta untuk mengorbankan diri demi masa depan. Jadi, masalah keadilan antar-generasi ini bukan sematamata masalah dalam masa transisi, namun juga muncul dalam konteks keadilan distributif. Paradoksnya adalah bahwa penyelidikan normalnya dilakukan terhadap fakta apakah generasi tua di masa kini mendapatkan keuntungan atas biaya generasi masa depan.103 Isu yang paling sering muncul biasanya berkaitan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam lainnya. Namun dalam kasus keadilan transisional, dalam masa pergeseran dari rezim represif ke liberal, masalah keadilan antar-generasi ini berbeda: generasi masa kini berkorban demi keuntungan generasi masa depan. Dalam konteks antar-generasi, sanksi atau penyitaan hak milik menjadi bentuk pengorbanan. Dalam masa transisi, pembersihan politik dan tindakan serupa sering kali dijustifikasi untuk kepentingan masa depan politik. Sering kali dikatakan bahwa dibutuhkan waktu panjang untuk menciptakan perubahan politik yang bertahan lama. Pada tingkat intuisi, jelas bahwa perjalanan waktu memiliki konsekuensi politik yang jelas. Praktik-praktik yang dibicarakan di atas menunjukkan penggunaan waktu sebagai dasar perubahan politik. Bila syarat lain diberikan terhadap tatanan politik, dengan perjalanan waktu, akan terdapat dampak bagi perubahan masyarakat dan politik. Perjalanan waktu, bila berdiri sendiri pun, dapat mempengaruhi transformasi politik. Keadilan Administratif Transisional Lustrasi, lustrace, epuracion, purifikasi, zwiering, rekonstruksi, demiliterisasi, depuración, apa pun istilah yang digunakan – praktik-praktik pembersihan transisional yang dibicarakan dalam bab ini menunjukkan bahwa penciptaan kondisi politik melalui hukum adalah hal yang endemik dalam masa transformasi politik. Praktik transisional menunjukkan banyaknya penggunaan hukum publik untuk mendefinisikan sistem politik yang baru. Untuk jangka 102 Memang ritual lustrasi dalam sejarahnya terkait dengan sensus. Lihat OED, entri “lustration”, definisi 3 dan 4, juga entri “lustrum”. 103 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1971, 284-93. 39 waktu tertentu, hukum publik yang bersifat sementara mendefinisikan ulang status dengan merekonstruksi pemahaman inti tentang pendukung dan penentang, tentang kawan dan lawan. Dalam berbagai masyarakat dan budaya hukum, pembersihan legal digunakan untuk melakukan perubahan politik. Tindakan publik radikal secara kritis merekonstruksi parameter komunitas politik, selain syarat partisipasi dalam tatanan politik yang berubah, karena pembersihan politik dan persyaratan lainnya memiliki imprimatur hukum, meskipun bersifat sementara. Tindakan-tindakan yang dibicarakan dalam bab ini bertentangan dengan intuisi kita tentang apa arti pergeseran menuju sistem liberal yang taat pada kedaulatan hukum: dengan ketidaktaatan pada prosedur, tiadanya prospektivitas, pendekatan yang cair terhadap tanggung jawab individu dan kolektif, dan terakhir, politisasinya secara eksplisit. Untuk Semua alasan ini, praktik-praktik dalam bab ini bertentangan dengan intuisi mendasar kita tentang liberalisasi. Pengakuan terhadap peran praktik-praktik ini dalam transisi menunjukkan ketiadaan nilai utama yang kaku dalam negara yang sedang melakukan liberalisasi, selain menarik perhatian kepada realitas politik di sekitar pembangunan negara liberal dari reruntuhan kediktatoran. Praktik-praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana rezim penerus boleh membentuk sistem administrasi atas dasar ideologi, dan mengekang kebebasan politik sampai terkonsolidasinya rezim yang lebih liberal. Sebagai titik awal, pertimbangkanlah apa yang diajarkan contoh-contoh dalam bab ini tentang bagaimana timbulnya tindakan-tindakan terpolitisasi ini; dalam transisi, pembersihan de facto di luar hukum sering kali mendahului pengaturannya. Tindakan ini bersifat tidak teratur, sebagian informal, sebagian lagi hukum formal. Dengan demikian, tindakan transisional menunjukkan bahwa dalam pergantian rezim, tidak hanya satu norma yang bisa diterapkan. Ini adalah fakta politik terpenting dalam buku ini: pergeseran rezim. Pergantian rezim politik dan pergeseran normatif yang menyertainya memunculkan sejumlah dilema ketaatan pada kedaulatan hukum. Tindakan administratif transisional yang dibicarakan di sini menengahi masa-masa gejolak politik radikal dalam merekonstruksi status, hak dan tanggung jawab dalam masyarakat yang melakukan transformasi politik. Meskipun negara-negara memiliki cukup kebebasan dalam membentuk sistem administrasinya, dalam masa biasa, pengambilan keputusan untuk hal tersebut biasanya tidak bersifat partisan. Tindakan terpolitisasi memungkinkan perubahan politik radikal dengan memberikan contoh, melakukan rekonstitusi politik melalui redistribusi hak-hak keanggotaan politik, representasi dan partisipasi secara cepat. Tindakan-tindakan ini merupakan alat revolusi karena memiliki kapasitas untuk membongkar struktur kekuasaan yang lama, dan mengkonsolidasikan rezim baru dalam pergerakan menuju liberalisasi. Meskipun berkaitan erat dengan kondisi politik transisi, tindakan-tindakan yang dibicarakan di sini juga bertentangan dengan pandangan normal tentang kaitan hukum dengan perubahan politik dan sosial. Sebagai awalnya, penggunaan hukum dan bukan keadilan jalanan merupakan respon terhadap pelanggaran di masa lalu yang terkendali dan mengikuti proses formal. Arahan proses hukum tidak semata-mata merupakan hasil dari kondisi politik, namun sejak awalnya merupakan bagian dari rencana transisional. Di sini hukum tidak hanya responsif, namun merupakan instrumen perubahan politik yang menimbulkan pergeseran kesetimbangan kekuasaan. Meskipun rezim liberal berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang terpisah dari politik dan tidak memiliki opini politik tertentu, tindakan-tindakan publik yang bersifat membatasi akan merekonstruksi negara itu. Tindakan transisional bersifat 40 terbatas, ia menunjukkan suatu masa luar biasa dalam sejarah negara, yang menunjukkan transisi. Penggunaan hukum secara radikal ini bisa menciptakan perubahan politik yang cepat dan berdampak luas. Dalam fungsi transformatifnya yang paling terpolitisasi, tindakan administratif bersifat kritis: repolitisasi terhadap lingkup publik merupakan respon kritis terhadap pemerintahan buruk di masa lalu. Respon terhadap diskriminasi politik dan liberalisasi dengan membongkar struktur negara lama, dan membalikkan hubungan kekuasaan yang lama. Bagaimana penggunaan praktik transisional melaksanakan transformasi? Praktikpraktik yang ditinjau di sini menunjukkan bahwa transformasi terjadi melalui pembalikan, rekombinasi bentuk-bentuk tradisional, melalui tindakan yang dibentuk sesuai kriteria kolektif, garis-garis ketidaksepakatan politik yang akan memungkinkan konsensus politik. Fungsi hukum yang paling transformatif ini, dalam praktik didelegasikan kepada badan negara lainnya, informal, memihak dan dipolitisasi. Hukum publik, cara yang paling sering digunakan negara modern untuk mencapai sasarannya, memiliki potensi lebih tinggi dalam masa perubahan radikal. Masa transisional menunjukkan hukum publik yang amat terpolitisasi, di mana penggunaan hukum bersifat simbolis, dan bergantung pada kekuatan retoriknya. Tindakan administratif transisional menjustifikasi sekaligus melaksanakan transformasi politik, dengan kekuatan yang besar karena mempengaruhi birokrasi. Pada masa gejolak politik, rezim pengaturan ini memungkinkan rekonstruksi publik terhadap ideologi politik yang baru. Melalui tindakan ini, rezim lama “diadili” secara politis; dan diciptakan standar baru untuk justifikasi publik dan rasionalisasi transisi normatif, rezim lama kehilangan legitimasi, ideologi lama dibantah dan yang baru mendapatkan legitimasi. Delegitimasi rezim lama dilakukan melalui rekonstruksi untuk membedakan siapa yang boleh berpolitik dan siapa yang tidak, melalui hukum publik. Melalui tindakan-tindakan ini, tatanan politik yang lama dibersihkan, dan tatanan politik yang baru diberi dasar loyalitas politik dan afiliasi. Pelarangan, pembersihan, sumpah kesetiaan, purifikasi, lustrasi, pengadilan dan publikasi, kesemuanya ini merupakan bentuk pernyataan publik yang memberikan dasar dan melaksanakan pergeseran normatif.104 Bentuk-bentuk ritual ini merupakan cara bagaimana hukum melakukan perubahan dalam hubungan kekuasaan untuk merekonstruksi komunitas politik dan menguji serta menyaring individu untuk menunjukkan kebenaran politik yang baru. Tindakan publik demikian menyusun rezim yang baru, membentuk dan melegitimasikan rezim penerus. Justifikasi politik (yaitu “tujuan-tujuan” hukum) untuk tindakan regulatoris transisional merupakan bagian dari politisasinya. Dengan menciptakan persyaratan politis, tindakantindakan demikian mentransformasikan identitas negara. Rekonstruksi hukum publik dalam kategori-kategori yang secara eksplisit merespon rezim politik lama menunjukkan transformasi transisional yang kritis. Pembongkaran tindakan penindasan kolektif – yang dilakukan berdasarkan ras, etnik atau religi – dilakukan dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan kriteria politik. Aturan-aturan lama dijadikan latar belakang, menunjukkan arti dan kekuatan normatif tindakan transisional. Transformasi politik ke arah liberal dalam rezim baru hanya dapat terlihat bila dilatarbelakangi identitas politik yang lama. Dalam konstruksi identitas nasional, garis-garis etnik, nasional atau agama mungkin bertentangan dengan pandangan liberal, namun negara-negara liberal bisa melakukan diskriminasi berdasarkan politik: terdapat kebebasan untuk menciptakan perundang-undangan yang membatasi opini 104 Lihat OED, entri “ban”. 41 politik. Pengambilan keputusan berdasarkan politik dalam lingkup publik sering kali bisa dikaitkan dengan kepentingan negara, yang dalam masa transisi akan menjadi semakin menonjol. Tindakan administratif transisional menantang intuisi kita tentang negara liberal, namun penggunaan tindakan demikian bukan tanpa justifikasi. Paradoks di sini, yang terlihat dalam tinjauan yudisial transisional, adalah bahwa liberalisasi dijadikan justifikasi untuk tindakan-tindakan tidak liberal. Tindakan-tindakan ini dijustifikasi oleh nilai-nilai yang mendasari prinsip-prinsip kedaulatan hukum yang terancam: kebebasan politik dan kesetaraan. Meskipun tindakan-tindakan demikian mengancam kedaulatan hukum konvensional, penggunaannya didukung oleh justifikasi bahwa mereka akan mengkonstruksikan negara liberal di masa yang akan datang. Tindakan administratif jangka pendek yang berbentuk radikal – terpolitisasi, memiliki cakupan yang luas dan kolektif – memberikan tantangan yang besar bagi kedaulatan hukum yang dikaitkan dengan negara liberal, melalui beberapa cara. Untuk awalnya, negara liberal memiliki aksioma bahwa warganya diperlakukan sebagai individu, dan bukan anggota kelompok atau secara askriptif; orang tidak bisa dipersalahkan karena menjadi anggota yang bertentangan dengan liberalisme. Intuisi liberal ini sering kali dianggap berlaku dalam transisi, ketika kebebasan baru dari penindasan berbasis komunal menimbulkan harapan untuk menghapuskan perbedaan berdasarkan kelompok. Namun, tindakan-tindakan yang dibicarakan dalam bab ini berbeda dari intuisi ideal liberal tersebut karena mempertahankan keputusan kolektif, tidak menjalankan due process individu, dan memilik prosedur yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal kedaulatan hukum dalam liberalisme. Bila tindakan administratif transisional memberikan sanksi pada satu kelas politik, ini merupakan keputusan yang politis. Intuisi kita tentang keputusan demikian adalah bahwa perilaku yang bisa dipidana relevan untuk dikaitkan dengan kemungkinan individu untuk berpartisipasi dalam negara liberal; sementara, keputusan secara kolektif bertentangan dengan dasar-dasar liberal tentang pertanggungjawaban individual. Namun, tindakan administratif transisional menjembatani individu dan kolektif, dan menciptakan perubahan pada tingkat struktural yang lebih luas dari sistem politik yang berubah. Tindakan ini tidak dapat dikategorisasikan dalam hukum konvensional. Tindakan administratif transisional merupakan gabungan hak, properti, reputasi dan hak politik; dalam suatu masa di mana tidak terdapat konsensus kemasyarakatan tentang status hak tersebut, dan bagaimana prosesnya harus dilakukan.105 Meskipun sanksi administratif sering kali dianggap sebagai bentuk “hukuman”, tidak seperti hukuman tradisional, prosedur demikian tidak membebankan tanggung jawab individu, namun suatu kelas politik yang harus bertanggungjawab. Apa pun harapan ideal tentang peran individu dalam negara liberal, ia tidak sesuai dengan masa transisi, ketika terdapat pemahaman transisional yang lebih cair tentang kaitan antara individu dan masyarakatnya. Dengan melakukan hal tersebut, tindakan-tindakan tersebut menjembatani perdebatan utama dalam transisi, tentang apakah respon terhadap pemerintahan yang buruk di masa lalu bersifat individual atau struktural.106 Dengan 105 Untuk eksplorasi terhadap pertanyaan ini, lihat Charles Reich, “The New Property”, Yale Law Journal 731 (1946): 733. 106 Untuk argumen yang menyarankan respon struktural, lihat Robert Gordon, “Undoing Historical Injustice”, dalam Austin Sarat dan Thomas R. Kearns (eds.), Justice and Injustice in Law and Legal Theory, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996. 42 penggunaan hukum publik secara luas, jurisprudensi transisional menciptakan perubahan individual dan struktural. Tindakan-tindakan ini menunjukkan signifikansi kedaulatan hukum inti: prospektivitas hukum, kaitan individu dan kolektif, dan peran politisasi dalam negara liberal. Studi hukum transisional yang dilakukan di sini menunjukkan ketegangan antara nilai-nilai kedaulatan hukum dan pendekatan individu dan kolektif dalam hukum. Ketegangan ini memunculkan bentuk-bentuk yang baru, yang bersifat transisional, memberikan batasan bagi hukum yang parsial, yang tidak menaati kedaulatan hukum sepenuhnya. Di sini terlihat bentuk penyelesaian dilema transisional yang paling sering yaitu tindakan yang bersifat sementara: tindakan transisional sering kali tidak berumur panjang dan tidak memiliki retrospektivitas maupun prospektivitas, yaitu membatasi suatu jangka waktu yang luar biasa. Denazifikasi dan purifikasi pasca-perang, Rekonstruksi pasca-Perang Saudara, lustrasi pasca-komunis Eropa Tengah dan Timur, dan tindakan pasca-junta, semuanya dirancang untuk jangka waktu yang terbatas, yaitu masa transformasi politik terbesar selama sekitar lima tahun setelah pergantian rezim. Dengan demikian, pembersihan ini menunjukkan transisi politik. Perundang-undangan yang terbatas ini dirancang untuk diterapkan pada jangka waktu politis yang terbatas. Penggunaan hukum publik yang dibicarakan di sini menunjukkan cara pikir tentang hukum administratif dalam jangka waktu tertentu. Dari perspektif historis dan komparatif, dalam berbagai budaya hukum, penggunaan hukum publik semakin meningkat berkaitan dengan masa-masa reformasi yang tinggi. Pendekatan empiris dari perspektif historis dan komparatif melampaui teori yang lazim tentang penggunaan hukum demikian. Penggunaan hukum untuk kepentingan transformatif melampaui realitas politik semata-mata, namun juga berbeda secara signifikan dari teori ideal yang ditarik dari sistem kedaulatan hukum yang sudah mapan. Tindakan konstitusional transisional seperti yang diambil setelah Perang Saudara dalam Rekonstruksi, dan Jerman-bersatu pasca-komunis menunjukkan kedekatan antara tindakan administratif dan konstitusional, yang akan dibicarakan dalam bab berikut. Praktikpraktik yang dibicarakan di sini berkaitan dengan jangka waktu yang singkat ketika terjadi transformasi politik yang paling signifikan, namun tindakan peralihan ini memiliki dampak yang panjang. Dengan tindakan ini, rekonstruksi keanggotaan, partisipasi dan kepemimpinan politik akan menimbulkan komitmen politik yang baru. Adalah hal yang lazim bahwa pejabat publik harus menjunjung norma-norma konstitusional sebagai syarat untuk menjabat, dan nilai-nilai demikian berlatar belakang hukum konstitusional. Di luar masa transisi, parameter politik struktural ini dianggap taken for granted, namun menjadi manifes dalam transisi. Dalam paru kedua abad ke-20, syarat normatif status, keanggotaan dan partisipasi politik telah menjadi bagian konstitusi secara nyaris universal untuk memandu kehidupan politik suatu negara. Pada masa gejolak politik, hukum publik regulatoris, seperti hukum konstitusional, berperan untuk mendefinisikan parameter normatif komunitas politik, syarat keanggotaan politik dan partisipasi dalam ranah publik. Tindakan transisional ini menunjukkan bahwa masa-masa perubahan politik menunjukkan dekonstitusionalisasi dalam latar belakangnya. Bahkan dalam ketiadaan konsensus konstitusional, tindakan administratif ini secara kritis mendefinisikan-ulang tatanan politik. 43 Bab 6 Keadilan Konstitusional Bab ini akan membahas sifat dan peran konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik. Dilema sentral dalam hal ini adalah bagaimana mendamaikan konsep konstitusionalisme dengan revolusi: masa-masa revolusi dan kelanjutannya adalah saat terjadinya gejolak politik, dan dengan demikian menimbulkan pertentangan dengan konstitusionalisme, yang lazimnya dianggap mengikat suatu tatanan politik yang mapan. Pertimbangkanlah klaim utama tentang kaitan konstitusionalitas dengan perubahan politik, dan terutama klaim modern tentang konstitusionalisme sebagai dasar demokrasi. Model ini paling tepat menjelaskan pandangan dari abad ke-18 tentang kaitan konstitusionalitas dengan hal-hal politis. Namun, model ini tidak dapat menggambarkan perkembangan konstitusional yang dikaitkan dengan perubahan politik selama setengah abad terakhir, sehingga memerlukan analisis tambahan.1 Bab ini menyelidiki manifestasi kontemporer dari konstitusionalisme, terutama dalam gelombang terakhir perubahan politik substansial, dan menunjukkan bahwa ia menimbulkan paradigma baru tentang konstitusionalisme transisional, yang memberikan tinjauan alternatif konstitusionalisme dalam usianya yang telah mencapai tiga abad ini. Paradigma alternatif yang dijelaskan di sini memiliki dampaknya di luar masa transisi untuk memahami konstitusionalisme, tinjauan yudisial dan prinsip penafsiran yang relevan. Konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik dikatakan memiliki kaitan “konstruktivis” dengan tatanan politik yang ada. Konstitusionalisme transisional tidak hanya diciptakan oleh tatanan politik yang ada, namun juga menciptakan perubahan. Inilah peran konstruktivis dari konstitusi. Konstitusi transisional dihasilkan dari berbagai proses, sering kali memiliki peran ganda: sebagai konstitusi konvensional, selain juga peran lain yang lebih radikal dalam transformasi politik. Penyusunan konstitusi transisional juga merespon pemerintahan lama, melalui prinsip-prinsip yang secara kritis menajamkan sistem politik yang baru dan mendorong perubahan politik lebih lanjut dalam sistem politik tersebut. Konstitusi transisional memandang ke belakang sekaligus ke depan, dan dilatarbelakangi oleh konsepsi keadilan konstitusional yang khas pada masa transisi. Model-Model Utama Penyusunan teori tentang sifat dan peran konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik lazimnya dipandu oleh perspektif realis atau idealis yang saling bertentangan. Dalam pandangan realis, konstitusi dalam masa perubahan politik dianggap hanya mencerminkan kondisi perimbangan kekuasaan politik yang ada, dan dengan demikian, 1 Tentang penyusunan konstitusi kontemporer, lihat Julio Faundez, “Constitutionalism: A Timely Revival”, dalam Douglas Greenberg et al. (eds.), Constitutionalism an Democracy: Transitions in the Contemporary World, New York: Oxford University Press, 1993, 354, 356. Lihat umumnya John Elster dan Rune Slagstad, Constitutionalism and Democracy: Studies in Rationality and Social Change, New York: Cambridge University Press, 1988 (kumpulan esai tentang kaitan konstitusionalisme dan demokrasi). 1 merupakan hasil dari perubahan politik.2 Dalam pandangan kaum realis ini, tidak jelas apa yang membedakan penyusunan konstitusi dengan perundang-undangan lainnya: apa arti khusus konstitusi dalam transisi? Dengan demikian, pandangan ini tidak memberikan banyak penjelasan tentang signifikansi sifat dan peran konstitusionalisme dalam masa demikian. Pendekatan dominan dalam studi konstitusionalisme dalam masa perubahan politik timbul dari teoretisasi idealis tentang konstitusi, di mana terdapat klaim normatif tentang kaitan kuat antara revolusi dan penyusunan konstitusi. Kaitan erat ini tampak pertama kali dalam model konstitusi klasik dalam tulisan Aristoteles. Meskipun pemahaman klasik ini tidak dianggap merupakan bagian dari model idealis dalam pandangannya tentang kaitan konstitusi dan perubahan politik, namun ia memiliki kedekatan dengan model ini. Ekspresi modernnya tampak dalam karya-karya Hannah Arendt, dan suatu artikulasinya dalam masa kontemporer dapat ditemukan dalam karya Bruce Ackerman, yang dibicarakan dalam bab ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek penting, namun klaim-klaim ini memiliki keserupaan dalam anggapan mereka tentang potensi penyusunan konstitusi untuk mengadakan perubahan politik. Di bawah ini akan dibahas pandangan-pandangan tersebut, sebagai suatu triad dalam sejarah politik konstitusional. Konstitusionalisme dalam masa-masa transformasi politik menimbukan pertentangan mendasar antara perubahan politik radikal dan batasan terhadap perubahan yang merupakan ciri dari tatanan konstitusional. Dalam model idealis yang akan dibahas di bawah ini, dilema ini diselesaikan dengan menyatakan bahwa konstitusi berfungsi sebagai dasar dari tatanan politik yang baru: suatu klaim fondasionalisme konstitusional. Pandangan Klasik Dalam pandangan klasik, konstitusi dianggap sebagai tatanan politik mendasar negara, organisasi khusus yang menentukan struktur dan fungsi negara. Dalam pandangan Aristotelian, konstitusi merupakan entitas organik: “‘Konstitusi’ negara merupakan organisasi dari badan-badan di dalamnya ...”.3 Dalam pemahaman ini, konstitusi bersifat normatif sekaligus deskriptif. “Asosiasi yang berupa negara ini eksis bukan agar anggotaanggotanya hidup bersama, namun untuk bertindak secara mulia”.4 Dengan demikian, dalam pandangan klasik, perubahan politik revolusioner memiliki arti perubahan konstitusi. Transformasi politik radikal tidak mewajibkan pergantian kepemimpinan, 2 Untuk teori-teori realis dalam politik, lihat Arendt Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries, New Haven: Yale University Press, 1984. Untuk studi kasus kontemporer, lihat Courtney Jung dan Ian Shapiro, “South Africa’s Negotiated Transition: Democracy, Opposition and the New Constitutional Order”, Policy and Society 23, 1995: 269. Untuk tinjauan realis tentang Konstitusi Amerika, lihat Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York: Macmillan, 1956. 3 Aristoteles, The Politics, terjemahan T. A. Sinclair, New York: Penguin Books, 1986. Lihat juga Charles H. MacIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca: Cornell University Press, 1947, (menjelaskan konsepsi kuno tentang konstitusi); Peter G. Stillman, “Hegel’s Idea of Constitutionalism”, dalam Alan S. Rosenbaum (ed.), Constitutionalism: The Philosophical Dimension, New York: Greenwood Press, 1988). 4 Aristoteles, The Politics, 198. 2 representasi atau keanggotaan, karena konstitusi-lah yang menentukan identitas suatu entitas politik. Bila konstitusi berubah, demikian pula entitas politik yang diaturnya: “Negara merupakan suatu bentuk asosiasi – asosiasi warga negara dalam bentuk konstitusi; sehingga bila konstitusi berubah dan menjadi berbeda, negara juga akan mengalami perubahan”.5 Tinjauan klasik terhadap politik konstitusional ini adalah konstitusionalisme organik. Dalam pandangan klasik, kesatuan antara revolusi dan konstitusi menengahi dilema yang disebabkan oleh kaitan antara konstitusionalisme dengan perubahan politik. Isu-isu keadilan tetap menjadi masalah, meskipun terdapat pergerakan ke arah tatanan yang lebih demokratis. Namun, pandangan ini mengarah ke pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa kaitan antara penyusunan-ulang konstitusi dengan perubahan politik? Bagaimana kesadaran konstitusional baru yang mendefinisikan transisi dapat terjadi? Paradigma klasik ini melahirkan, namun tidak menjelaskan, teori tentang peran konstitusionalisme dalam proses perubahan politik. Klaim Modern Berbeda dari pandangan klasik, teori konstitusional modern menekankan batasan normatif terhadap kekuasaan negara terhadap hak-hak struktural dan individual. Namun, beberapa aspek dalam konseptualisasi klasik tetap dipertahankan dalam model modern ini, paling tidak dalam pandangan tentang sifat dan peran konstitusi dalam masa perubahan politik. Pandangan klasik menyetarakan konstitusi dengan tatanan politik, dengan implikasinya terhadap sifat dan peran utama konstitusi dalam masa perubahan politik. Peran paradoksal dari konstitusi-konstitusi modern adalah bahwa mereka dianggap memberikan pembatasan bagi pemerintahan meskipun dalam masa perubahan politik. Bagaimana cara mendamaikan pandangan modern tentang konstitusionalisme dengan perubahan konstitusional? Inilah dilema konstitusionalisme dalam konteks perubahan politik massif. Bagi Hannah Arendt, dilema ini diselesaikan dengan memikirkan ulang teori konstitusionalisme. Alih-alih mengkonseptualisasikan penyusunan konstitusi sebagai hal yang kontrarevolusioner dan merupakan kebalikan dari perubahan politik, “elemen yang paling revolusioner dari penyusunan konstitusi” adalah “peletakan dasar”.6 Pandangan Arendt ini banyak merujuk pada penyusunan konstitusi Amerika. Dalam versi ini, dilema antara revolusi dan konstitusi tidak terlihat: kedua tindakan politik ini merupakan satu kesatuan. Konstitusi dianggap sebagai puncak revolusi: ia adalah “usaha dari seluruh bangsa untuk menciptakan badan politik yang baru”.7 Pandangan Arendtian ini menyelesaikan pertentangan antara revolusi dan konstitusionalisme melalui pemikiran tentang dasar (foundation). Para revolusioner di Amerika digambarkan sebagai para “peletak dasar” yang berusaha untuk menciptakan suatu dasar yang abadi. Dalam penyusunan konstitusi, tujuan mereka adalah “keinginan 5 Ibid., 176. Hannah Arendt, On Revolution, New York: Viking Press, 1965, 142. Untuk tinjauan sejarah tentang perkembangan konstitusionalisme sejak Perang Saudara di Inggris hingga awal abad ke-20, lihat M.J.C Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford: Clarendon Press, 1967. 7 Arendt, On Revolution, 143. 6 3 untuk menciptakan Kota Abadi di bumi”, dan keinginan untuk membentuk pemerintah “yang mampu menghentikan siklus pergantian pemerintahan, dari menanjaknya hingga keruntuhan suatu imperium, dan membentuk suatu kota yang abadi”.8 Pemikiran tentang peletakan dasar ini menyelesaikan dilema perubahan politik dengan konstitusi yang bersifat abadi. Meskipun bersifat paradoksal, perubahan revolusioner yang ingin dilakukan ini adalah tindakan peletakan dasar yang bersifat konstitutif. Konstitusionalisme Amerika dicirikan oleh paradoks perubahan konstitusional: yang revolusioner namun berlangsung abadi. Pandangan Amerika terhadap revolusinya ini mendorong timbulnya paradigma baru tentang konstitusionalisme sebagai dasar bagi tatanan demokratik. Dalam paradigma ini, konstitusionalisme adalah sesuatu yang berbeda dari arti klasiknya, yang diidentifikasikan dengan tatanan politik. Ia lebih menyerupai konstitusionalisme dalam arti Magna Carta, yang melindungi kebebasankebebasan negatif. Pemikiran tentang demokrasi konstitusional melampaui perlindungan terhadap hak-hak individual saja. “Penyusunan konstitusi” dianggap sebagai “tindakan revolusioner yang paling utama dan mulia”.9 Suatu konstitusionalisme mendasar yang ideal memiliki potensi untuk mengesahkan seluruh sapuan normatif dari revolusi. Melanjutkan pemikiran Arendt, konstitusionalis Amerika, Bruce Ackerman, menyatakan klaim normatif yang kuat tentang penyusunan konstitusi sebagai dasar revolusi demokrasi. Dalam pandangan ini, penyusunan konstitusi merupakan tahap terpenting dan terakhir dalam revolusi liberal, suatu “momen konstitusional” revolusioner yang menunjukkan keterpisahan dari rezim lama dan berdirinya tatanan politik yang baru.10 “Jika sasaran yang ingin dicapai adalah tranformasi terhadap norma-norma konstitusional, maka keterpisahan sama sekali adalah hal yang diharapkan ...”. Bagi Ackerman, suatu “tatanan yang sah” bergantung pada “usaha sistematik untuk menunjukkan prinsip-prinsip rezim baru”. Dalam teori konstitusional kontemporer, penyusunan konstitusi transformatif tidak terbatas pda revolusi; namun terdapat pula momen-momen konstitutif lainnya yang potensial. Dengan memperluas kemungkinan penyusunan konstitusi transformatif di luar masa revolusi, Ackerman memberikan suatu perbedaan antara politik biasa dan politik konstitusional dalam model modern ini. Dalam kerangka “demokrasi dualis”, perubahan politik atau konstitusi normal berjalan dalam jalur yang berbeda, dan menawarkan penyelesaian yang rapih terhadap dilema yang ditimbulkan konstitusionalisme dalam masa-masa revolusioner. Dengan mendefinisikan kategori “ganda” yaitu penyusunan keputusan “biasa” oleh pemerintah, dan penyusunan hukum “tingkat tinggi” oleh “rakyat”, dilema konstitusi dan perubahan politik radikal dapat diselesaikan.11 Dalam demokrasi dualis, dilema awal konstitusional, perubahan konstitusional dan tinjauan konstitusional dihilangkan. Dalam model kontemporer, penyusunan konstitusi memiliki arti revolusi melalui penyusunan hukum tingkat tinggi, namun pembedaan antara penyusunan hukum tingkat tinggi dan rendah masih ambigu. Yang mencirikan penyusunan hukum tingkat tinggi adalah suatu proses yang khas dan penentuan waktu yang tepat. Ada saat-saat yang 8 Ibid., 232-34. Ibid,. 157. 10 Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992, 57. Lihat umumnya Michel Rosenfeld (ed.), Constitutionalism, Identity, Difference and Legitimacy: Theoretical Perspectives, Durham: Duke University Press, 1994 (menganalisis kaitan antara konstitusionalisme dan identitas kelompok). 11 Bruce A. Ackerman, “Constitutional Politics/Constitutional Law”, Yale Law Journal 99 (1989): 453-547. 9 4 dianggap tepat sebagai saat penyusunan konstitusi, suatu jangka waktu penyusunan konstitusi atau “momen konstitusional”. Penyusunan konstitusi dilakukan sebelum pengesahan hukum dan institusi lainnya.12 Penyusunan hukum tingkat tinggi juga berimplikasi proses pengambilan keputusan yang lebih teliti. “Jalur penyusunan hukum tingkat tinggi ... menggunakan prosedur khusus untuk menentukan apakah mayoritas rakyat memberikan dukungannya terhadap prinsip-prinsip dari suatu gerakan revolusioner yang akan dinyatakan dengan mengatasnamakan rakyat”.13 Kaum fondasionalis memandang bahwa status khusus politik konstitusional ini berasal dari peran kedaulatan rakyat di dalam penyusunannya, melalui proses penyusuannya yang khusus. Politik konstitusional dianggap berkaitan dengan tingkat pertimbangan politis yang lebih tinggi, dan dengan demikian berbeda dari perpolitikan biasa. Konsepsi ini merujuk pada proses berdirinya Amerika Serikat, bahwa konvensi konstitusional Amerika ini memiliki konsensus luas. Namun klaim ini agak kontroversial. Mungkin proses-proses yang dianggap sebagai syarat fondasionalisme konstitusional perlu diinterpretasikan pada tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, kurangnya partisipasi dalam proses ratifikasi konstitusi bukanlah hal yang fatal, selama partisipasi dalam hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi politik biasa dalam masa itu. Suatu perspektif transisional membantu menjelaskan mengapa dalam masamasa gejolak politik, bahkan partisipasi terbatas dari masyarakat sudah cukup untuk melegitimasi transformasi konstitusional.14 Dalam paradigma kontemporer utama, terdapat klaim kuat tentang kaitan antara perubahan politik dan perubahan konstitusional. Pemikiran ideal tentang konstitusi bersifat memandang ke depan: tujuannya adalah untuk meninggalkan masa lalu dan bergerak menuju masa depan yang lebih cerah. Penyusunan konstitusi dianggap menjadi dasar bagi tatanan demokratis yang baru. Meskipun klaim-klaimnya dianggap berlaku universal, teori konstitusional kontemporer sendiri ditarik dari suatu konteks politik tertentu, yaitu revolusi di abad ke18. Sementara pemahaman modern tidak menganggap konstitusi sebagai tatanan politis suatu negara, seperti dalam pemahaman klasik, pandangan modern tentang politik konstitusional tak terlepaskan dari revolusi di masa lalu dan tatanan politik masa depan. Meskipun pengalaman Amerika dianggap mencontohkan penyusunan konstitusi yang mendasar, dalam tahun-tahun terakhir, suatu klaim preskriptif yang lebih luas juga diarahkan kepada negara-negara lain dalam proses transisi. Maka, dalam The Future of Liberal Revolution, pandangan fondasionalis diperluas ke transisi pasca-komunis kontemporer. Dengan merujuk pada proses penyusunan konstitusi Amerika Serikat, Ackerman menyerukan kepada negara-negara demokrasi baru di Eropa Timur agar menyisihkan politik biasa dan memuncakkan revolusi mereka dengan suatu konstitusi.15 Namun pandangan tentang konstitusi sebagai dasar perubahan politik yang liberal hanya menawarkan penyelesaian teoretis terhadap dilema penyusunan konstitusi pasca-revolusi. 12 Ibid., 55. Ibid., 14 14 Lihat Peter Berkowitz, “Book Review”, Eighteenth Century Studies 26 (1993): 695 (meninjau Bruce A. Ackerman, We the People: Foundations, Cambridge: Harvard university Press, Belknap Press, 1991 (menunjukkan bahwa pemilihan umum untuk meratifikasi konstitusi biasanya diikuti oleh hanya sedikit pemilih). 15 Lihat Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, 193. Untuk argumen kontinental yang terkait, lihat Ulrich Preuss, Constitutional Revolution: The Link Between Constitutionalism and Progress, terjemahan Deborah Lucas Schneider, Atlantic Highlands: Humanities Press, 1995. 13 5 Lebih lanjut lagi, meskipun terdapat kontribusi teori konstitusional kontemporer terhadap perdebatan dalam ilmu politik tentang kriteria perubahan menuju liberalisasi, buku ini menganggap bahwa perubahan politik menuju liberalisasi terkait dengan berbagai respon legal, di luar respon konstitusional. Model dominan ini amat teridealisasi, dan dengan demikian, tidak dapat menjelaskan berbagai fenomena konstitusional yang terkait dengan masa-masa transformasi politik. Sebaliknya, konstitusionalisme kontemporer memerlukan pemikiran ulang terhadap teori dominan tentang kaitan perubahan politik dan perubahan konstitusional. Preseden konstitusional pada akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa model ini terlalu membedakan antara politik biasa dan politik konstitusional. Seperti dijelaskan di bawah, konstitusionalisme pada masa perubahan politik radikal menunjukkan berbagai manifestasi politik konstitusional. Suatu Kontra-Tinjauan Transisional Bagian ini menunjukkan suatu tinjauan terhadap konstitusionalisme transisional dari sudut pandang yang berbeda, untuk menangkap dengan lebih baik perpolitikan konstitusional yang dikaitkan dengan masa-masa transformatif. Konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik radikal mencerminkan transisionalitas dalam prosesprosesnya, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan-perkembangan dalam masamasa gejolak politik. Penyusunan konstitusi (seperti dibicarakan di bawah) sering kali diawali dengan konstitusi sementara, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan konstitusi yang lebih permanen. Meskipun terdapat anggapan tentang hukum konstitusional sebagai bentuk hukum yang paling memandang ke depan dan abadi, penyusunan konstitusi transisional sering kali tidak permanen dan menunjukkan perubahan bertahap. Banyak dari konstitusi yang disusun dalam masa perubahan politik radikal secara eksplisit direncanakan untuk bersifat sementara. Sementara teori utama membayangkan konstitusi sebagai sesuatu yang monolitik dan abadi, konstitusi transisional memiliki beberapa ciri yang menunjukkan kesementaraannya, sedangkan ciri-ciri lainnya menjadi lebih mapan seiring berjalannya waktu. Model “konstruktivistik” yang diajukan di sini memiliki kesamaan dengan proses yang ditunjukkan dalam bentuk teridealisasi dalam teori Rawls tentang penciptaan konsensus politik secara bertahap. John Rawls menggunakan istilah konstruktivisme politik untuk menggambarkan timbulnya konsensus konstitusional secara bertahap sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan secara bertahap yang menyempitkan ruang perbedaan antar-partai politik. Analisis di sini bersifat konstruktivistik pula dalam hal yang berbeda. Sama seperti pemikiran Rawls, pemikiran di sini menyatakan bahwa elemen-elemen konstitusional secara bertahap muncul melalui proses politik seiring perjalanan waktu. Namun, pemikiran di sini menganggap bahwa semua perubahan dalam tatanan konstitusional menimbulkan perubahan perspektif para partisipan, dan dengan demikian mengubah anggapan mereka tentang apa yang diizinkan dalam politik, dengan konsekuensinya terhadap potensi konsensus konstitusional.16 Transisionalitas ini menimbulkan beberapa implikasi normatif. Dalam teori yang umum diterima, konstitusionalisme dianggap bersifat satu arah, memandang ke depan 16 Bandingkan dengan John Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, 9099 (mendefinisikan “konstruktivisme politik”). 6 dan sepenuhnya prospektif. Bila pemahaman politik retrospektif dicantumkan, bentuk ideal ini tidak tepat digunakan untuk menjelaskan fenomena konstitusional transisional. Sementara gambaran tentang suatu masyarakat politik pada titik nol konstitusional tepat untuk menggambarkan konstitusionalisme di abad ke-18, pada masa kontemporer, konstitusi yang disusun sebagai akibat perubahan politik lazimnya menggantikan rezim konstitusional yang telah ada, dan bukan hal yang sama sekali baru. Konstruksi tatanan konstitusional baru dalam masa peruahan politik radikal didukung oleh konsepsi transisional tentang keadilan konstitusional. Hukum konstitusional biasanya dianggap sebagai bentuk hukum yang paling memandang ke depan. Namun, konstitusionalisme transisional bersifat ambivalen; bagi generasi revolusioner, prinsip-prinsip keadilan konstitusional di dalamnya berkaitan dengan ketidakadilan di masa lalu. Dari perspektif transisional, apa yang dianggap adil secara konstitusional bersifat kontekstual dan terkait dengan pelanggaran di masa lalu. Studi tentang konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik menunjukkan bahwa berbagai bentuk transisi akan menimbulkan perbedaan dalam hal kontinuitas konstitusional. Tipe-tipe konstitusi yang dipaparkan di sini, seperti tipe ideal Weber, tidak menggambarkan seluruh fenomena konstitusional yang ada, namun membantu memahami berbagai keragaman fenomena konstitusional. Mereka juga mencerminkan berbagai respon legal transisional lainnya yang memiliki modalitasmodalitas serupa. Bab-bab lain dalam buku ini telah membicarakan respon-respon legal transisional dalam bentuk ajudikatif dan punitif. Dengan modalitas kodifikasi, konstitusionalisme lebih mengekspresikan konsensus yang ada, alih-alih tujuan yang transformatif. Sementara, dalam modalitas transformatif, dalam konstitusionalisme kritis, konstitusi yang baru secara eksplisit merekonstruksi tatanan politik yang dikaitkan dengan ketidakadilan. Dalam bentuk transformatif yang lain, yaitu penggunaan konstitusi baru untuk mengembalikan tatanan konstitusional sebelum rezim pelaku pelanggaran, konstitusi demikian dapat dianggap bersifat restoratif. Bila konstitusi baru merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, manifestasi kontinuitas konstitusional ini dapat dianggap “residual”. Seperti akan ditunjukkan dalam tinjauan perkembangan konstitusi dalam masa-masa perubahan politik, banyak konstitusi transisional mencerminkan aspek-aspek dari berbagai tipe di atas. Konstruksi konstitusi yang demikian dapat memediasi masa-masa perubahan politik. Dalam bab ini akan diinterpretasikan bagaimana terjadinya pergeseran dari pemerintaan non-liberal ke rezim yang lebih liberal, dan peranan konstitusi dalam konstruksi perubahan politik tersebut. Di bawah ini terdapat sejumlah kasus yang menggambarkan sifat dan peran konstitusionalisme dalam masa-masa transformasi politik. Fenomena konstitusionalisme transisional telah ada sejak masa kuno, yaitu konstitusi baru setelah revolusi Athena. Dengan terjadinya revolusi, timbul perdebatan tentang sistem politik baru yang diharapkan, yang berakhir dengan dua rancangan konstitusi, untuk masa krisis jangka pendek dan untuk “masa depan”.17 Dengan transisi historis demikian, timbul dilema tentang mengaitkan perubahan politik revolusioer dengan penyusunan konstitusi. Seperti akan terlihat, proses konstitusional bertahap demikian terjadi pula dalam transisi kontemporer. 17 Lihat Aristoteles, The Athenian Constitution, terjemahan P.J. Rhodes, New York: Penguin Books, 1984, bab 29-33. 7 Pergeseran dari Pemerintahan Otoriter Dalam teori kontemporer, pandangan ideal tentang konstitusi adalah sebagai puncak revolusi dan dasar tatanan demokratis yang baru. Konstitusi dianggap melampaui sifatnya yang terpolitisasi, karena perpolitikan konstitusional melampaui perpolitikan biasa. Sebaliknya, dalam model realis, sifat dan peran konstitusi dalam transisi yang timbul dari negosiasi sangatlah dipolitisasi, dan konstitusi dianggap sebagai perpanjangan dari politik biasa.18 Kedua pendekatan ini bertentangan dalam memandang tempat konstitusionalisme dalam politik transformatif. Namun, keduanya tidak dapat menerangkan sifat politik konstitusional dalam perubahan politik kontemporer. Peran konstitusi dalam masa pascaotoritarianisme menunjukkan paradigma politik radikal, ia juga membantu mengkonstruksi keterbukaan politik yang memungkinkan terjadinya transisi. Konstitusi transisional menengahi pergeseran politik dari pemerintahan otoriter. Mereka mengkonstruksi masa-masa peralihan berupa perubahan politik substansial, meskipun tidak sepenuhnya demokratis. Konstitusi demikian bersifat transisional dalam beberapa aspek: prosesnya bersifat transien (bertahan hanya untuk sementara waktu), dan instrumennya pun sebagiannya bersifat sementara. Konstitusi demikian sering kali masih mengandung unsur-unsur dari rezim konstitusional pendahulunya, yang dapat dianggap residual. Contoh konstitusi demikian tampak dalam transisi historis ternegosiasi di Eropa, selain dalam gelombang perubahan politik kontemporer. Meskipun perang merupakan titik balik terpenting yang dianggap sebagai batasan untuk membangun dasar konstitusional, pergeseran politik sering kali terjadi tanpa titik balik tersebut, sebagai hasil negosiasi politik yang berkepanjangan. Konstitusi transisional dapat diciptakan dalam pergeseran dari pemerintaan otoriter sebagai hasil perundingan. Bila rezim pendahulu belum runtuh dan pergeseran politik hanya tercapai setelah terjadi negosiasi, konstitusi memainkan peran yang tidak banyak dijelaskan oleh teori konstitusional yang lazim diterima. Konstitusi transisional tidak semata-mata menghentikan revolusi, namun juga berperan dalam membentuk transisi. Pada tahap awal proses ini, konstitusi dapat mendorong perubahan politik. Peran konstitusi transisional yang mendestabilisasi tatanan politik yang telah ada ini dapat dianalogikan dengan peran konstitusi pada masa biasa yang memapankan tatanan politik. Suatu gambaran kontemporer konstitusi yang membongkar tatanan politik adalah konstitusi Afrika Selatan pasca-apartheid. Konstitusi pasca-apartheid ini diibaratkan sebagai “suatu jembatan bersejarah yang mengaitkan masa lalu suatu masyarakat yang terbelah yang dicirikan oleh pertikaian, konflik, penderitaan luar biasa dan ketidakadilan, dengan masa depan yang didirikan oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, demokrasi dan koeksistensi damai ... bagi semua warga Afrika Selatan”.19 Dengan wataknya yang seperti itu, konstitusi Afrika Selatan pasca-apartheid memberikan contoh 18 Lihat umumnya Juan J. Linz dan Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996 (suatu tinjauan tentang langkah-langkah transisi), 10. Lihat juga Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. 19 Konstitusi Afrika Selatan, bab 15, § 251 (“Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi”). Tatanan konstitusional lainnya yang mencerminkan kompromi politik demikian berkaitan dengan keberlanjutan kekuasaan eksekutif, yang diawasi dewan eksekutif transisional. 8 penggunaan konstitusi transisional setelah berakhirnya pemerintahan otoriter. Konstitusi ini mengandung kesepakatan politik dan pergeseran dari pemerintahan oleh minoritas terhadap mayoritas warga yang tidak memiliki hak politik, ke sistem demokrasi perwakilan. Pakta konstitusional ini memungkinkan terjadinya transformasi politik. Sejauh mana legitimasi konstitusional yang baru ini bisa didapatkan dari suatu kesepakatan yang diratifikasi parlemen era apartheid? Sejauh mana kaitan prosedural dengan rezim lama akan melemahkan proses konstitusional? Akar konstitusi transisional dalam rezim apartheid ini tidak lagi menjadi masalah besar karena sifatnya yang sementara. Perubahan konstitusional diawali dengan pengesahan konstitusi sementara oleh parlemen lama, yang disahkan dengan syarat akan disusun sebuah konstitusi lain yang prospektif. Pembukaan konstitusi 1993 sendiri menjelaskan bahwa ia akan berlaku sampai konstitusi yang final diberlakukan.20 Konstitusi transisional Afrika Selatan 1993 mencerminkan modalitas yang kompleks. Sementara pada umumnya bersifat sementara, ia juga mengandung prinsipprinsip konstitusional yang mengikat. Dalam strukturnya, konstitusi pasca-apartheid ini memiliki kemiripan dengan konstitusi Jerman pasca-perang.21 Meskipun bersifat transisional, undang-undang dasar Jerman memiliki pasal-pasal inti tentang identitas politik liberal negara tersebut. Prinsip-prinsip yang mengikat ini berkaitan dengan kesetaraan dan hak-hak perwakilan. Dengan menegaskan perlindungan terhadap kelompok etnik dan ras, konstitusi Afrika Selatan mentransformasi peninggalan sejarah prasangka rasial dengan bergerak meninggalkan penindasan dan sistem apartheid, dan menetapkan nilai-nilai konstitusional yang liberal.22 Konstitusi transisional terutama berguna dalam pergeseran dari pemerintahan militer. Dalam transisi di Eropa Selatan, misalnya, konstitusi 1978 pasca-Franco 20 Pembukaan Konstitusi Afrika Selatan menyatakan: “Dengan demikian diperlukan suatu provisi untuk mendorong kesatuan nasional dan restrukturisasi dan Pemerintahan Afrika Selatan yang berkelanjutan sementara suatu Dewan Konstitusional hasil pemilihan umum menyiapkan Konstitusi final”...(tekanan ditambahkan). 21 Rencana konstitusi kedua dianggap tidak sah oleh Pengadilan Konstitusional negara tersebut, berkaitan dengan prinsip-prinsip penggerak dalam konstitusi tersebut. Lihat In re Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (4) SALR 744 (CC) (Afrika Selatan). Konstitusi final disahkan tidak lama sebelum buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris. Bandingkan dengan Pasal 79(3) Undang-Undang Dasar jerman (klausul tentang kepermanenan). 22 Schedule 4 menyatakan beberapa “prinsip konstitusional” yang tidak boleh diubah atau ditentang oleh konstitusi berikutnya, seperti: Konstitusi harus melarang diskriminasi ras, gender dan segala bentuk diskriminasi lainnya dan harus mendorong kesetaraan rasial dan gender serta kesatuan nasional. .... Sistem hukum harus menjamin kesetaraan semua orang di muka hukum dan proses hukum yang tidak memihak. Kesetaraan di muka hukum mencakup hukum, program dan aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mereka yang tertindas, termasuk mereka yang tertindas karena dasar ras, warna kulit atau gender. Konstitusi sementara Afrika Selatan, Akta 209 tahun 1993, sched. 4, pts. III dan V, dicetak ulang dalam Dion Basson, South Africa’s Interim Constitution: Text and Notes, Kenwyn, Afrika Selatan: Juta and Company, 1994. Cara kerja proses konsolidasi konstitusional ini dijelaskan dalam keputusan Pengadilan Konstitusional yang membatalkan rencana konstitusi berikutnya. Lihat catatan kaki 21 9 membantu mengarahkan Spanyol untuk menghindari pemerintahan militer.23 Transisionalitas konstitusi ini dicerminkan dari tiadanya pencabutan kekuasaan militer secara mutlak; meskipun militer harus menaati pemerintahan konstitusional, banyak dari struktur pembagian kekuasaan yang baru masih belum didefinisikan. Meskipun pertanyaan kunci dalam transisi Portugal pada tahun 1974 adalah tentang tempat militer dalam rezim baru, angkatan bersenjata negara itu memainkan peran menentang kediktatoran dan mendatangkan liberalisasi. Dengan menciptakan struktur konstitusional yang memberikan tempat bagi angkatan bersenjata, konstitusi pasca-revolusi yang pertama memungkinkan transisi menuju demokrasi dengan merestrukturisasi alokasi kekuasaan sipil dan militer.24 Di seluruh Amerika Latin, konstitusi transisional menjadi penengah antara rezim militer dan sipil.25 Dengan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan negara yang memungkinkan terjadinya pelanggaran di masa lalu, struktur otoriter direkonstruksi untuk mengadakan transformasi politik.26 Konstitusi Brazil 1988 diakui bersifat sementara: setelah lima tahun. diharapkan akan diadakan tinjauan terhadap konstitusi dan melakukan amendemen. Berdasarkan teori konstitusional yang lazim, sifat sementara dari konstitusi ini seharusnya tidak sesuai dengan tujuan utama konstitusi tertulis, yaitu untuk memelihara suatu pandangan tertentu tentang kekuasaan negara selama jangka waktu 23 Lihat Andrea Bonime-Blanc, Spain’s Transition to Democracy: The Politics of Constitution-Making, Boulder: Westview Press, 1987, 31; Jordi Solé Tura, “Iberian Case Study: The Constitutionalism of Democratization”, dalam Douglas Greenberg et al. (eds.), Constitutionalism and Democracy: Transition in the Contemporary World, New York: Oxford University Press, 1993, 292-94. Lihat umumnya O’Donnell dan Schmitter, Transitions: Tentative Conclusions, 37-72. Penundukan militer terhadap kekuasaan sipil masih belum lengkap, karena konstitusi masih memberikan tugas kepada militer untuk melindungi tatanan konstitusional. Menurut pasal 104 Konstitusi Spanyol: Pasukan dan Korps Keamanan yang merupakan alatalat Pemerintah akan bertugas melindungi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan secara bebas dan menjamin keamanan warga ... Suatu hukum organik akan menentukan fungsi, prinsip dasar untuk bertindak dan Statuta pasukan dan Korps Keamanan. 24 Untuk tinjauan tentang transisi, lihat Kenneth Maxwell, “Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal”, dalam Guillermo O’Donnell et al. (eds), Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 108-37. Lihat Tura, “Iberian Case Study”, 291-92. 25 Untuk tinjauan umum tentang transisi dan analisis terhadap Konstitusi 1988, lihat Keith S. Rossen, “Brazil’s New Constitution: An Exercise in Transient Constitutionalism for a Transitional Society”, American Journal of Comparative Law 38 (1990): 773. 26 Untuk contoh tentang batasan baru terhadap penetaan keadaan siaga, lihat Pasal 136 dan 137, selain penyusunan undang-undang kepresidenan yang dikaitkan dengan keadaan darurat. Konstitusi Brazil menyatakan: “Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres Nasional “... Konstitusi Brazil, Pasal 44. Pasal 62 menyatakan: Dalam kasus penting dan urgen, Presiden Repblik bleh mengambil tindakan sementara yang berkekuatan hukum; namun, ia harus segera memberikannya kepada Kongres nasional, yang bila sedang dalam keadaan reses, harus bersidang dalam sidang istimewa dalam waktu lima hari. .... Tindakan semantara ini akan tidak berlaku sejak tanggal diterbitkannya bila tidak diubah kedudukannya menjadi hukum dalam tiga puluh hari setelah tanggal diterbitkannya, dan Konres Nasional harus mengatur semua hukum yang terkait yang mungkin timbul dari pengambilan langkah-langkah tersebut. 10 yang panjang.27 Namun dari perspektif transisional, kritik ini tidak tepat. Jika sebuah rezim politik masih belum mapan, tidak logis untuk menekankan kemutlakan konstitusi. Kemungkinan untuk terjadinya reformasi yang dikaitkan dengan konstitusi interim pertama sering kali disyaratkan pada penundaan proses konstitusional yang diikuti oleh lebih banyak aktor politik. Konstitusi kontemporer Cili secara dramatis menunjukkan kemungkinan ini. Konstitusi 1991 membantu mengangkat negeri tersebut dari kediktatoran militer, dengan biaya yang harus dibayar oleh konstitusi. Konstitusi transisional pertama mempertahankan kontinuitas residual dengan pemerintahan yang baru saja berlalu, dengan mengakomodasi kediktatoran militer dalam struktur konstitusional. Dalam sejumlah amendemen konstitusional yang dilakukan secara berhati-hati, dan dinegosiasikan oleh junta militer yang berkuasa, dan oposisi politik, timbul harapan untuk mengembalikan demokrasi ke Cili. Amendemen konstitusional membatasi kekuasaan militer dan institusi yang mendukung kekuasaan militer, dan mencabut larangan terhadap partai oposisi dalam Senat. Perubahan transisional ini memungkinkan pembagian kekuasaan antara sipil dan militer, dan pergeseran menuju rezim demokrasi dan liberal.28 Reformasi konstitusional bertahap yang serupa terjadi di Argentina, di mana hanya setelah terjadi dua kali pergantian pemerintaan, konstitusi baru dapat disahkan. Bahkan, konstitusi 1994 yang baru ini masih mempertahankan beberapa pasal dari Konstitusi 1853, meskipun mengganti beberapa bidang yang memerlukan perubahan, seperti batasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, konstitusi baru ini mencerminkan gabungan dari ciri-ciri “residual” dan “kritis”. Kolombia memberikan gambaran historis tentang perubahan konstitusional yang memberikan batasan antara dua rezim. Dianalogikan dengan sebuah traktat, konstitusi Kolombia yang baru memungkinkan terjadinya perdamaian. Suatu krisis politik yang berkepanjangan antara pemerintah dan para gerilya meledak pada dekade 1980-an dengan keruntuhan negara secara parsial.29 Krisis politik ini menandakan perlunya perbaikan terhadap konstitusi, namun masalahnya adalah bagaimana melaksanakan reformasi konstitusional tanpa adanya dukungan Kongres dan dengan ketidaktaatan terhadap hukum-hukum konstitusional yang sudah ada. Kolombia meninggalkan prosedur konstitusionalnya yang sudah lazim untuk memungkinkan perubahan konstitusional sementara, sebelum dilakukan reformasi konstitusional yang lebih menyeluruh. Dengan referendum tentang perubahan konstitusional, keputusan diambil untuk memilih dewan konstitusional untuk mengubah konstitusi. Referendum ini diikuti pemilihan anggota dewan tersebut. Pada saat tersebut, para mantan gerilyawan telah melakukan demobilisasi, menunjukkan peran penting sebagai kekuatan independen dalam 27 Untuk contoh argumen ini, lihat Rossen, “Brazil’s New Constitution”, 783. Untuk tinjauan singkat tentang negosiasi yang terjadi, lihat “Chile: Chronology 1988-1991”, jilid 4 dalam Albert P. Blaustein dan Gilbert H. Flanz (eds.), Constitutions of the Countries of the World, Dobbs Ferry, N.Y: Oceana Publications, 1994, 33-36. Pasal 9 tentang partai politik mengalami amendemen, selain Pasal 95 dan 96, yang melemahkan Dewan Keamanan nasional. 29 Daniel T. Fox dan Anne Stetson, “The 1991 Constitutional Reform: Prospects for Democracy and the Rule of Law in Colombia”, Case Western Reserve Journal of International Law 24 (1992): 143-44. 28 11 perpolitikan dan pemilihan umum, dan akhirnya akan berperan penting dalam penyusunan konstitusi.30 Hal-hal itu membentuk proses transisi; mereka memberikan ruang politik dan membatasi proses politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Konstitusi Kolombia merupakan contoh mekanisme konstruktif dalam transformasi politik. Dengan sifatnya yang secara sadar ditetapkan sementara, ia ditujukan untuk merestrukturisasi tatanan politik yang labil. Karena pelanggaran-pelanggaran terberat terjadi dalam pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif, konstitusi baru memberikan kekuasaan legislatif yang luar biasa kepada presiden, dan juga membentuk “kongres mini” untuk bertugas selama kongres yang baru belum terbentuk. Aturan-aturan sementara diberlakukan untuk mengatur pemilihan umum bebas yang pertama, membentuk tatanan politik yang baru, memberikan amnesti bagi kejahatan di masa lalu,31 dan mengintegrasikan para mantan gerilyawan. Konstitusionalisme memiliki arti keterlepasan dari masa lalu, dan kemudian diikuti penggabungan kembali ke dalam sistem politik yang baru. Konstitusi transisional yang dibicarakan di atas secara eksplisit memiliki kepentingan politis, karena mereka semua meratifikasi berbagai ciri kesepakatan politik yang sering kali berjalan bersama dengan konstitusi transisional dan juga mengarahkan perubahan konstitusional. Fakta bahwa kesepakatan tersebut sering kali tidak dicapai berdasarkan partisipasi politik secara luas menentang asas demokrasi dalam penyusunan konstitusi tersebut. Bahkan, sifat terpolitisasi konstitusi tersebut tampak jelas dalam kemiripannya dengan tindakan pidana transisional. Dalam pergeseran dari pemerintahan yang kejam, konstitusi transisional sering kali meratifikasi amnesti terhadap pelanggaran politik di masa lalu. Peran kesepakatan amnesti transisional dalam menengahi transisi telah dibahas dalam bab 2 tentang peradilan pidana. Maka, dalam masa transisi, konstitusi menggariskan batasan terhadap hal-hal yang boleh dipolitisasi dan apa yang tidak. Dalam konteks perubahan politik, konstitusi tidak hanya merupakan puncak atau tahapan akhir dari revolusi, namun menjadi alat dalam penciptaan transformasi. Dengan demikian, ia sering kali merupakan mekanisme sementara yang memfasilitasi transformasi politik. Konstitusi transisional menunjukkan kesepakatan dan struktur politik sementara, dan menciptakan ruang politik yang baru untuk mengkonstruksikan transisi politik. Lebih lanjut lagi, dengan dikukuhkannya beberapa norma konstitusional yang penting, konstitusi transisional bisa menjadi respon konstruktif terhadap pemerintahan represif di masa lalu. Sementara sifat transisional konstitusi ini terutama berkaitan dengan struktur kekuasaan negara, prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan norma-norma hak individual dimaksudkan menjadi bersifat transformatif dan abadi, yang memandu identitas demokrasi liberal negara. Terdapat suatu hukum tingkat tinggi, yang bahkan lebih tinggi dari konstitusi, yang bisa dianggap sebagai “konstitusi dari konstitusi”. 30 William C. Banks dan Edgar Alvarez, “The New Colombian Constitution: Democratic Victory of Popular Surrender?” University of Miami Inter-American Law Review 23 (1991): 55-57. Lihat Foz dan Stetson, “The 1991 Constitutional Reform”, 142, 145. 31 Lihat Konstitusi Kolombia, Pasal Peralihan 6 (menjelaskan Konstituante Nasional), Pasal Peralihan 39 (memberikan kepada presiden “kekuasaan luar biasa” untuk menerbitkan “keputusan yang berkekuatan hukum” dalam jangka waktu tiga bulan), dan Pasal Peralihan 30 (tentang amnesti). 12 Penyusunan konstitusi transisional, hingga batasan tertentu, mencerminkan ideide yang lazim tentang negara dan perubahan politik. Tidak seperti model konstitusional yang dominan, konstitusi transisional bersifat fleksibel dalam mengukuhkan normanorma, seperti terlihat dalam tahapan-tahapan konstitusional sementara yang berkaitan dengan isu-isu konstitusional yang kontroversial. Seiring perjalanan waktu, perubahan pada konstitusi akan mengubah lingkup politik lebih lanjut, yang mendorong perubahan konstitusional. Paradigma konstitusional konstruktivistik yang dibicarakan di sini berakar pada analisis komparatif terhadap praktik politik dalam masa transisi dan pemikiran induktif, dan memiliki kemirian dengan beberapa model teoretik proses pembangunan konsensus konstitusional secara bertahap.32 Akhirnya, alih-alih mengekspresikan konsensus masyarakat yang sudah ada, prinsip-prinsip normatif dalam konstitusikonstitusi ini paling bisa dijelaskan dalam tinjauan transisional, karena tujuannya mencerminkan kemungkinan penggunaan konstitusi untuk transformasi. Keadilan Konstitusional sang Pemenang Arah penyusunan konstitusi setelah berakhirnya perang tampaknya mengikuti aturan ideal pemutusan dari masa lalu dan peletakan awal yang baru. Meskipun konstitusionalime pasca-perang menuntut adanya pemutusan dari masa lalu, tidak berarti bahwa model konstitusional ini selalu melalui proses-proses demokratis dan menjunjung kedaulatan rakyat. Dua ilustrasi yang dibicarakan di sini adalah Jerman Barat dan Jepang pasca-perang, yang mensahkan skema konstitusionalnya setelah kemenangan Sekutu dan penyerahan tanpa syarat. Konstitusi Jerman maupun Jepang sama-sama menggambarkan konstitusionalisme yang jelas-jelas transisional, yaitu “konstitusi sang pemenang”. Hingga titik tertentu, konstitusi ini dipaksakan. Tujuan transisional konstitusi pascaperang ini terlihat dalam beberapa fungsi kritisnya: seperti tercermin dalam mandat substantifnya, Undang-Undang Dasar Jerman dan Konstitusi 1946 Jepang dirancang untuk mentransformasi peninggalan represif di masa lalu. Mungkin kasus paling ekstrem dari keadilan konstitusional pemenang adalah konstitusi pasca-perang Jepang. Dengan disahkan di bawah dominasi Amerika, dan dirancang oleh suatu kelompok kecil di bawah arahan Jenderal Douglas MacArthur, dan dipaksakan kepada parlemen Jepang untuk ratifikasi,33 konstitusi Jepang 1946 tidak bisa dianggap sebagai suatu ekspresi kedaulatan rakyat dalam konteks pendudukan ini. Signifikansi partisipasi masyarakat dalam penyusunan konstitusi tidak terlalu besar dalam negara-negara yang memiliki tradisi pemerintahan otoriter. Seperti konstitusi MacArthur, konstitusi Meiji sebelumnya juga dirancang oleh beberapa anggota elite. Meskipun awalnya tidak demokratis, otoritas konstitusi yang masih berlanjut ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa mekanisme lain yang melegitimasi konstitusi pemenang seiring perjalanan waktu. Hingga titik tertentu, konstitusi pemenang di Jepang ini merupakan versi yang ekstrem dari proses konstitusional yang dalam abad ke-20 lazim terjadi dalam transisi. Dalam masa transisi politik, setelah perang atau pemerintahan represif, proses 32 Lihat Rawls, Political Liberalism, 133-72. Untuk tinjauan mendalam tentang sejarah penyusunan konstitusi Jepang, lihat Kyoko Inoue, MacArthur’s Japanese Constitution: A Linguistic and Cultural Study of Its Making, Chicago: University of Chicago Press, 1991. 33 13 konstitusional sering kali dimoderatori oleh pasukan pendudukan atau negara-negara yang berpengaruh. Mungkin bentuk intervensi yang paling moderat adalah peran penasihat konstitusional yang dimainkan oleh aktor internasional, nasional atau NGO.34 Tingkat intervensi aktor-aktor ini mempengaruhi bagaimana proses penyusunan konstitusi ini dapat dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat. Mungkin legitimasi konstitusi pasca-perang bergantung pada mandatnya dan sejauh mana proses konstitusional tersebut dapat mengembangkan norma-norma demokratis untuk membentuk struktur politik dalam transisi. Dalam hal ini, banyak bagian dari konstitusi 1946 yang mencerminkan modalitas transisional yang bersifat transformatif dan kritis. Tujuan eksplisit konstitusi tersebut adalah untuk mengubah kecenderungan politik ke arah militerisme dan nasionalisme imperialistik. Kekuasaan Jepang untuk menyatakan perang dihilangkan sama sekali, dan peran kaisar diturunkan, dari semula setengah dewa menjadi hanya figur.35 Terdapat usaha secara luas untuk menggantikan rezim legal yang lama dan menggerakan Jepang menuju sistem formal demokrasi egaliter.36 Konstitusi 1946 Jepang menunjukkan beberapa aspek kritis dalam memberikan respon retributif terhadap rezim lama. Pembatasan terhadap kekuasaan kaisar tampak sebagai alternatif jelas terhadap peradilan pidana. Respon ini menunjukkan kemiripan antara peradilan pidana dan penyusunan konstitusi dalam masa-masa gejolak politik. Seperti didiskusikan lebih awal, konstitusi sering kali digunakan untuk mengakui pelanggaran pidana di masa lalu, sekaligus mengampuninya. Dalam kondisi demikian, konstitusi menarik garis untuk membatasi parameter politik demokratis yang dimungkinkan. Dengan membatasi kekuasaan kaisar, konstitusi baru memberikan kompromi terhadap ancaman penghukuman yang mendestabilisasi peran kekaisaran.37 Seperti pengadilan para raja di abad ke-18, batasan konstitusional terhadap kedaulatan kekaisaran menggariskan batasan normatif antara pemerintahan lama dengan rezim baru. Penyusunan konstitusi demikian, seperti pengadilan, memberikan legitimasi publik dan formal terhadap transformasi dari sistem politik lama.38 Keadilan sang pemenang tidak berjalan sepenuhnya di Jerman. Meskipun Jerman menyerah tanpa syarat, perubahan politik dalam Perang Dingin memberikannya posisi tawar dalam rekonstruksi konstitusionalnya. Penguasa pendudukan memang mendorong, namun tidak mengendalikan rekonstruksi konstitusional. Maka, meskipun Sekutu menyerukan agar suatu badan konstituante bersidang untuk merancang konstitusi yang akan disahkan melalui plebisit umum, Jerman menentang tuntutan untuk menyusun 34 Untuk suatu tuduhan bahwa konstitusi gagal menciptakan otoritas dan stabilitas, lihat Arendt, On Revolution, 144-45. 35 Lihat Konstitusi Jepang, Bab III, Pasal 9. Bab I Konstitusi Jepang membahas perihal kekaisaran. Dalam Pasal 1, ia dijadikan “simbol negara”. Pasal 3 menyatakan: “Saran dan persetujuan Kabinet akan menjadi syarat untuk semua tindakan kaisar dalam hal kenegaraan, dan kabinet akan bertanggung jawab”. Pasal 4 menyatakan: “Kaisar ... tidak memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan”. 36 Misalnya, Pasal 14 dalam Bab I menyatakan: “Semua warga setara di muka hukum dan tidak akan terdapat diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi dan sosial karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau akar keluarga ... Kebangsawanan tidak akan diakui ... Tidak ada privilese yang diberikan bersama semua bentuk penghargaan ...” 37 Lihat Ian Buruma, The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan, New York: Farrar, Strauss, Giroux, 1994, 153-76. 38 Lihat umumnya Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crime Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986, 257-82 (mendaftar sumbersumber pengadilan kejahatan perang di Asia). 14 konstitusi permanen, dan mensahkan Basic Law yang dirancang untuk bersifat transitoris, untuk “menciptakan tatanan baru dalam kehidupan politik dalam masa transisional”. Basic law ini dirancang untuk diratifikasi oleh badan legislatif, dengan proses pleno untuk penyusunan konstitusi ditunda hingga setelah rencana reunifikasi, namun momen konstitusional ratifikasi ini tidak pernah terjadi.39 Dalam model konstitusional yang lazim, kesementaraan Basic Law ini tidak dapat dijelaskan dengan baik. Namun, paradigma konstitusionalisme transisional dapat menjelaskan provisionalitas Basic Law ini dan komitmen normatifnya. Tujuan utamanya bersifat transformatif: untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan oleh rezim lama.40 Dengan demikian, Basic Law mengikuti model konstitusi kritis yang dijelaskan di atas. Tidak seperti konstitusi abad ke-18, dalam Basic Law, norma-norma konstitusional tentang ancaman terhadap demokrasi tidak hanya mencakup penyalahgunaan kekuasaan, namun mencapai kebijakan kekuasaan itu sendiri. Hal ini paling dapat dijelaskan melalui perspektif transisional. Arti keadilan konstitusional dalam perspektif transisional dikonseptualkan dan dikonstruksi berdasarkan rezim konstitusional dan politik yang mendahuluinya. Di Jerman, pelajaran dari Republik Weimar mengarahkan pemikiran konstitusional masa pasca-perang. Keberhasilan fasisme dianggap timbul dari skema konstitusional Weimar, yang menggabungkan eksekutif yang kuat dan legislatif yang lemah, yang memungkinkan timbulnya gerakan subversif. Untuk merespon hal ini, Basic Law secara agresif melawan kecenderungan fasis dalam tatanan politik yang berpuncak pada kediktatoran Nazi. Dalam Basic Law, kekuasaan kepresidenan dijadikan simbolis. Serupa dengan cara konstitusi Jepang pasca-perang memperlakukan kaisar, presiden Federal di Jerman tidak diberi kekuasaan; kekuasaan disebarkan kepada parlemen.41 Seperti juga konstitusi Jepang, Basic Law Jerman juga mencerminkan bagaimana mekanisme pidana dan konstitusional memberikan respon alternatif bagi pemerintahan yang buruk di masa lalu. Baik penghukuman maupun penyusunan konstitusi memberikan batasan normatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara seperti di masa lalu. Kedaulatan baru akan tercapai ketika Sekutu menghentikan proses pengadilan pendudukan dan Jerman memberikan komitmen untuk menyusun konstitusi.42 Basic Law Jerman melarang penindasan rasial dan religius yang banyak terjadi pada masa rezim Nazi. Misalnya Pasal 3 (3) menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diprasangkai atau diberikan keuntungan karena jenis kelamin, keturunan ras, bahasa, daerah asal, kepercayaan atau opini agama dan politiknya”.43 Sementara hak-hak kesetaraan demikian lazim terdapat dalam konstitusi modern, Basic Law memberikan perlindungan lebih dari sekadar 39 Lihat Basic Law for the Federal Republic of Germany (1949), diterjemahkan dalam Peter H. Merkl, The Origin of the West German Republic, New York: Oxford University Press, 1963, app. 213, hal. 319. Lihat juga Klaus H. Goetz dan Peter J. Cullen (ed.), Constitutional Policy in Unified Germany, Portland, Ore: Frank Cass, 1995 (kumpuan artikel tentang konstitusionalisme Jerman). 40 Lihat Merkl, Origin of the West German Republic, 22-24, 80-89. 41 Bab V, berjudul “Presiden Federal”, tersusun oleh delapan pasal. Pasal 61 berkaitan dengan impeachment. Basic Law for the Federal Republic of Germany, diumumkan oleh Dewan Parlementer, 23 Mei 1949, dicetak ulang dalam Flanz, Constitutions of the World, jilid 7, Dobbs Ferry, N.Y: Oceana Publications, 1996. 42 Untuk tinjauan historis, lihat Frank M. Buscher, The War Crimes Trial Program in Germany, 1946-1955, New York: Greenwood Press, 1989, 161. 43 Basic law, Pasal 3(3). Pasal 4(1) menyatakan: “Kebebasan beragama dan berpikir bebas dan kebebasan menyatakan agama dan falsafah hidup tidak boleh dilanggar”. 15 perlindungan konvensional. Struktur normatif yang diciptakan oleh Basic Law sering kali dikatakan sebagai “demokrasi militan”.44 Demokrasi militan mungkin merupakan konsep yang paradoksal, namun menunjukkan tujuan transformatif utama dari instrumen ini. Dengan memberikan persyaratan demokratis bagi individu dan partai politik, elemen-elemen non-liberal akan disingkirkan dari kehidupan politik. Suatu tatanan konstitusional yang militan tidak hanya siaga menghadapi penyalahgunaan kekuasaan negara, tetapi juga kedaulatan rakyat.45 Konstitusionalisme transisional berjalan secara berbeda dari intuisi umum tentang peran konstitusionalisme. Perlindungan terhadap penindasan serupa di masa depan tidak terbatas pada pernyataan tentang hak-hak individual; konstitusi transisional tidak hanya memberikan batas terhadap mayoritas politik, namun juga pada sistem politik yang tidak liberal. Pandangan bahwa fasisme merupakan ekspresi politik yang bersifat populis mengarah pada usaha untuk membatasi ekspresi demikian, bahkan bila dilakukan oleh mayoritas sekalipun, yang merupakan suatu tindakan paradoksal dalam usaha mempertahankan demokrasi konstitusional. Sebagai instrumen konstitusional sementara, Basic Law mencerminkan berbagai tingkat transisionalitas dan kekokohan konstitusional. Beberapa norma konstitusional bersifat sementara, sedangkan yang lainnya yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai normatif liberal (seperti perlindungan hak kesetaraan individual) bersifat amat kukuh dan tidak dapat diutak-atik,46 dan dengan demikian mendefinisikan identitas politik liberal negara tersebut. Basic Law Jerman, seperti diinterpretasikan pengadilan konstitusional negara itu, menjadi penjaga negara liberal. Ia bisa dibandingkan dengan konstitusi pascaapartheid Afrika Selatan 1993. Konstitusi pasca-perang ini menggambarkan konstitusionalisme dalam abad ketiganya. Dalam pergeseran meninggalkan pemerintahan otoriter, dengan latar belakang rezim konstitusional yang sudah ada, konstitusi demikian memainkan fungsi kritis: merekonstruksi kecenderungan konstitusional masa lalu yang terkait dengan kebijakan non-liberal. Sementara penyusunan konstitusi pasca-otoritarianisme sering kali tidak memiliki legitimasi melalui proses konstitusional penuh yang ada dalam model fondasionalis, delegitimasi terhadap rezim yang lama membuka jalan untuk rekonstruksi konstitusional. Konstitusi pasca-perang tidak dapat dijelaskan dalam model konstitusional yang diidealisasi, karena tidak bisa dianggap sebagai ekspresi sepenuhnya konsensus masyarakat dan agenda revolusioner. Sering kali bahkan konstitusi merupakan hasil proses politik yang bertentangan dengan itu. Ketiadaan konsensus masyarakat dalam proses penyusunan konstitusi dan ketiadaan komitmen demokratis yang terdapat dalam pandangan tentang konstitusi sebagai dasar politik juga tampak dalam prinsip 44 Lihat Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, edisi kedua, Durham: Duke University Press, 1997. Untuk ilustrasi tentang prinsip konstitusional ini dalam Keputusan Pengadilan Konstitusional Federal, lihat, Socialist Reich Party Case, 2 BverfGE 1 (Jerman 1952), diterjemahkan dalam Kommers, Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 218. Lihat juga Donald P. Kommers, “German Constitutionalism: A Prolegomenon”, Emory Law Journal 40 (1991): 854. 45 Partai-partai politik yang “tujuannya atau tindakan pengikutnya, berusaha untuk melemahkan atau menyingkirkan tatanan mendasar demokrasi bebas atau mengancam eksistensi Republik Federal Jerman, dianggap inkonstitusional”, Basic Law, Pasal 21 § 2. Individu kehilangan hak konstitusionalnya untuk berekspresi bila terjadi penyalahgunaan ucapan, pers, pendidikan dan berkumpul “untuk melemahkan tatanan mendasar demokrasi bebas” (Pasal 18). Lihat bab sebelumnya “Keadilan Administratif”. 46 Lihat Basic Law, Pasal 74 § 3 (menetapkan bahwa “prinsip-prinsip mendasar” dalam Pasal 1 dan 20 tidak boleh diamendemen :hingga jangka waktu yang tidak terbatas” atau “abadi”). 16 normatif konstitusi-konstitusi tersebut. Konstitusi modern biasanya dirancang sebagai struktur untuk membatasi kekuasaan negara, namun konstitusi transisional melawan kecenderungan tidak liberal secara lebih luas. Dalam teori realis, konstitusi dapat dijelaskan melalui perimbangan kekuasaan. Namun, anggapan tentang konstitusionalisme sebagai produk perimbangan kekuasaan tidak dapat menjelaskan transisi total, seperti setelah berakhirnya perang, penyerahan tanpa syarat dan keruntuhan rezim lainnya. Baik model idealis maupun realis mengasumsikan bahwa kemenangan rezim revolusioner terhadap rezim pendahulunya memiliki arti bahwa penyusunan konstitusi akan sepenuhnya memandang ke depan. Namun, karena struktur normatif konstitusional tersebut tidak dijelaskan oleh tipe ideal atau penjelasan berdasarkan perimbangan kekuasaan masa kini, mereka menunjukkan suatu model konstitusi transisional yang khas. Revolusi Damai dan Konstitusinya Apa implikasi bagi konstitusionalisme revolusi damai? Seperti dalam banyak transisi pasca-otoritarianisme, keruntuhan komunisme terjadi setelah jatuhnya rezim komunis yang berkuasa, atau perubahan politik sebagai hasil negosiasi.47 Perubahan politik di bekas blok Soviet pada umumnya terjadi secara damai, perubahan konstitusional di kawasan ini tidak mengikuti model dominan yang berpola pada revolusi gaya abad ke-18. Revolusi damai demikian biasanya tidak memiliki satu titik balik (pemutusan) dengan rezem lama, sehingga tidak berpuncak pada perubahan konstitusional secara mendasar. Bertahun-tahun setelah perubahan politik, di sebagian besar negara di kawasan tersebut, terdapat kontinuitas konstitusional. Yang terjadi adalah munculnya konstitusionalisme transisional yang menunjukkan aspek-aspek residual. Bahkan negara-negara yang berada dalam tahapan reformasi ekonomi yang lebih lanjut masih bergantung pada dokumendokumen era komunis yang telah direvisi.48 47 Lihat Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1979, 23-24. Tentang transisi Eropa Timur, lihat umumnya Timothy Garton Ash, The Magic Lantern: The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, New York: Random House, 1990; Ivo Banac (ed.), Eastern Europe in Revolution, Ithaca: Cornell University Press, 1992; John Feffer, Shock Waves: Eastern Europe after the Revolutions, Boston: South End Press, 1992,dan Ken Jowitt, New World Disorder: The Leninist Distinction, Berkeley: University of California Press, 1992. 48 Hongaria, misalnya, masih menggunakan konstitusi era Soviet yang telah diperbaiki. Lihat Andrew Arato, “The Constitution Making Endgame in Hungary”, East European Constitutional Review 5 (musim gugur 1996): 31. Lihat umumnya Péter Paczolay, “The New Hungarian Constitutional State: Challenges and Perspectives”, dalam A. E. Dick Howard (ed.), Constitutional Making in Eastern Europe, Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, 1993, 21; Edith Otlay, “Toward the Rule of Law – Hungary”, Radio Free Europe and Radio Liberty Research Report (1992): 16. Dalam sebagian besar masa transisinya, Polandia menggunaan Konstitusi Kecil, suatu konstitusi sementara yang hanya menjelaskan struktur umum sistem politik. Lihat Andrzej Rapaczynski, “Constitutional Politics in Poland: A Report on the Constitutional Committee of the Polish Parliament”, University of Chicago Law Review 58 (1991): 595. Baru pada bulan April 1997 dicapai konsensus tentang konstitusi baru. Lihat Andrzej Rzeplinski, “The Polish Bill of Rights and Freedoms: The Case Study of Constitution-Making in Poland”, East European Constitutional Review 2 (musim panas 1993): 26. Lihat juga Wiktor Osiatynski, “A Bill of Rights for Poland”, East European Constitutional Review 1 (musim gugur 1992): 29. Di Rusia, perdebatan tentang legitimasi parlemen era Soviet dan konstitusi mengarah pada krisis yang berpuncak pada keputusan 17 Apa yang diakibatkan perubahan politik yang mulus – atau revolusi damai – terhadap perubahan konstitusional? Bila revolusi dengan kekerasan memiliki arti pemutusan dengan rezim konstitusional lama, revolusi damai berarti terdapat kontinuitas. Dilema ketegangan antara konstitusionalisme dan perubahan politik menjadi hilang, karena tidak terdapat diskontinuitas. Seperti dalam transisi hasil negosiasi lainnya, konstitusi berperan dalam meratifikasi kesepakatan yang mengkonstruksi pergeseran politik,49 selain mengembalikan tatanan konstitusional dari masa sebelum revolusi.50 Konstitusionalisme pasca-komunis menunjukkan beberapa kemiripan antara teori perubahan politik yang berlangsung seperti “domino” setelah keruntuhan Soviet, demikian pula terjadi pada perubahan konstitusionalisme. Perubahan konstitusional terjadi melalui negosiasi, bukan melalui kedaulatan rakyat. Sebaliknya, perubahan konstitusional yang pertama terjadi melalui tawar menawar antara elite-elite politik. Dalam revolusi damai, rezim pendahulu tidak diruntuhkan, namun diturunkan dengan hati-hati. Amendemen konstitusional digunakan untuk meratifikasi pergeseran dari satu rezim politik ke rezim politik lainnya. Dalam transisi ternegosiasi, perubahan konstitusional pertama adalah untuk mencabut tatanan kekuasaan. Di seluruh kawasan ini, amendemen konstitusional digunakan untuk mencabut privilese partai komunis. Proses amendemen di Hongaria dan Polandia, misalnya, langkah pertamanya adalah mencabut kekuasaan dari partai komunis yang dominan, dan melindungi partai-partai minoritas. Jadi, perubahan konstitusional pasca-komunis lebih berkaitan dengan pembatasan kekuasaan partai daripada pembatasan kekuasaan negara. Di sini terdapat kemiripan dengan Basic Law Jerman, dan respon konstitusional terhadap totalitarianisme. Babak pertama perubahan konstitusional ini bersifat sementara, mencerminkan kemiripan dengan respon legal transisional lainnya. Proses konstitusional di wilayah ini bukanlah tahap puncak dalam perubahan revolusioner, namun terkait erat ekstrakonstitusional. Lihat umumnya Dwight Semler, “The End of the First Russian Republic”, East European Constitutional Review 3 (musim dingin 1994): 107; Vera Tolz, “The Moscow Crisis and the Future of Democracy in Russia”, Radio Free Europe and Radio Liberty Research Report (1993): 1. Di Estonia, pemilihan umum di tahun 1992 diadakan sesuai konstitusi 1938 yang komunis. Pemilihan presiden dan anggota parlemen pada tanggal 20 September 1992 dijalankan sesuai dengan aturan dalan Konstitusi 1938. Lihat “Constitutional Watch”, East European Constitutional Review 1 (musim gugur 1992): 2, 5. Di Albania, hingga tahun 1994, konstitusi baru belum disahkan. Lihat Constitutional Watch: East European Constitutional Review 3 (musim semi (1994): 2. “Undang-Undang tentang Perihal Konstitusional yang Utama” yang bersifat sementara masih tetap berlaku. 49 Lihat umumnya Paczolav, “New Hungarian Constitutional State”, 21; Jon Elster, “Constitutionalism in Eastern Europe: An Introduction”, University of Chicago Law review 58 (1991): 447 (tinjauan dan analisis terhadap transisi menuju demokrasi konstitusional di Eropa Timur). Bagi sebagian besar negara di bekas blok Soviet, pergeseran menuju rezim yang dipilih secara demokratis dilakukan melalui pembicaraan antara partai komunis dengan oposisi. Lihat umumnya Jon Elster (ed.), The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago: University of Chicago Press, 1996 (tinjauan mendalam tentang proses tawar menawar yang memungkinkan transisi). Di Hongaria, proses penyelesaian negosiasi dengan penyusunan rancangan konstitusi berlangsung dalam proses yang selalu terancam runtuhnya konsensus politik. Dengan demikian, proses amendemen konstitusi tidak dilakukan melalui pertimbangan yang panjang, dan segera diputuskan oleh Parlemen yang mensahkan amendemen tersebut. Lihat Arato, Constitution-Making Endgame in Hungary, 685. 50 Lihat András Sajó, “Preferred Generations: A Paradox of Restoration Constitutions”, Cardozo Law Review 14 (1993): 853-57. Untuk diskusi tentang fenomena kontinuitas konstitusional di Eropa Tengah dan Timur, lihat umumnya Preuss, Constitutional Revolution, dan Andrew Arato, “Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern Europe”, dalam Michel Rosenfeld (ed.), Constitutionalism, Identity, Difference and Legimacy, Durham: Duke University Press, 1994, 165. 18 dengan proses politik yang bertahap. Perubahan konstitusional seperti itu terkait dengan perubahan politik, sehingga tidak dapat dipisahkan. Namun, legitimasi perubahan di Hongaria secara jelas digambarkan “transisonal”, juga amendemen terhadap konstitusi era Stalin di Polandia dikatakan sebagai “Konstitusi Kecil”. Lima tahun setelah revolusi, Polandia dan Hongaria akhirnya mengadakan perubahan konstitusional yang mendalam, mengarah ke suatu deklarasi tentang hak-hak asasi.51 Alih-alih mengikuti model ideal penyusunan konstitusi sebagai ekspresi mendasar konsensus politik yang sudah ada, di sini amendemen konstitusional dilaksanakan paling awal, yang meletakkan dasar untuk perubahan politik lebih lanjut. Jadi, konstitusionalisme revolusi damai menantang pemahaman fondasionalis tentang kaitan antara konstitusi dan revolusi. Satu wajah lain dari konstitusionalisme pasca-komunis adalah konstitusionalisme “restoratif”. Di bekas Cekoslowakia, revolusi dimulai pada bulan November 1989, dengan demonstrasi memperingati lima puluh tahun penutupan universitas-universitas di Cekoslowakia oleh pasukan pendudukan Jerman. Hal ini menggarisbawahi nilai historis pendudukan politik di wilayah tersebut. Pada akhir pendudukan politik, terdapat dorongan untuk kembali ke tatanan konstitusional yang telah ada sebelum pendudukan. Oleh penulis, dimensi dari konstitusionalisme transisional ini dikatakan sebagai “konstitusionalisme restorasi”.52 Di blok bekas komunis, konstitusionalisme restorasi banyak terjadi, menunjukkan keinginan untuk kembali ke rezim konstitusional sebelum era komunis. Di bekas Cekoslowakia, Konstitusi 1920 menjadi dasar rancangan untuk konstitusi “baru” setelah revolusi. Di Latvia, elemen-elemen konstitusi 1922 beserta undang-undang yang disahkan oleh parlemen telah berlaku sejak bulan Mei 1990. Konstitusi 1938 menjadi dasar rancangan konstitusi baru di Estonia, dan dasar rancangan konstitusi Georgia adalah konstitusi 1921.53 Kembali ke konstitusi restorasi ini memungkinkan negara-negara tersebut mampu menghindari rezim konstitusional yang terkait dengan komunisme. Namun, beberapa negara kembali ke struktur konstitusional restoratif ini hanya karena nostalgia dan keinginan untuk mencapai stabilitas. Bahkan, penggunaan istilah restorasi ini menunjukkan adanya tarikan normatif dari tatanan lama. Namun, restorasi pasca-komunis diragukan memberikan stabilitas. Meskipun rezimrezim ini merupakan ekspresi identitas tradisional dan nasional, mereka tidak bisa dianggap mencerminkan konsensus sosial yang ada. Namun, konstitusi restorasi memiliki daya tarik normatif yang bisa menghindarkan dilema awal konstitusional. Dengan konstitusionalisme restorasi, tidak ada awal yang baru, hanya kembali ke tatanan yang telah ada. Konstitusionalisme demikian menghilangkan ketegangan yang terdapat dalam konstitusionalisme dalam masa perubahan politik. 51 Tentang Hongaria, lihat “Constitution Watch: Hungary”, East European Constitutional Review 5 (musim dingin 1996): 10, tentang Polandia, lihat “Constitution Watch: Poland”, East European Constitutional Review 5 (musim dingin 1996): 16-17. 52 Restorasi memiliki kemiripan dengan perubahan “reaksioner”. Lihat Albert O. Hirschman, The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1991, 110 (tentang perubahan “reaksioner”). 53 Lihat Lloyd Cutler dan Herman Schwartz, “Constitutional Reform in Czechoslovakia: E Duobus Unum?” University of Chicago Law Review 58 (1991): 531-36; Constitution Watch: Latvia”, East Euroean Constitutional Review 2 (musim semi 1993): 8-9; “Constitution Watch: Estonia”, East Euroean Constitutional Review 1 (musim gugur 1992): 5; Rancangan Konstitusi Georgia (arsip Center for the Study of Constitutionalism in Eastern and Central Europe, University of Chicago). 19 Kasus-kasus ini menggambarkan berbagai modalitas konstitusionalisme transisional. Bila terdapat perubahan konstitusional, ia tidak berlangsung melalui lembaga atau prosedur khusus, namun secara bertahap, melalui negosiasi dan proses politik biasa. Perubahan konstitusional demikian tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan politik. Banyak bagian dari tatanan konstitusional baru ini bersifat residual, mencerminkan kontinuitas konstitusional. Perubahan konstitusional yang transformatif dalam hal ini sering berarti kembali ke tatanan politik dan konstitusional yang sudah ada sebelum totalitarianisme, suatu bentuk konstitusionalisme restorasi. Konstitusi Amerika: Tinjauan Transisional Akhirnya, kita akan membahas konstitusi Amerika, contoh utama dalam paradigma penyusunan konstitusi fondasional. Meskipun memiliki status ini, kasus Amerika ini tidak sepenuhnya sesuai dengan model teoretik yang dominan, sehingga menunjukkan bahwa model ini tidak lengkap dan harus ditunjang dengan model lainnya. Pengisahan kembali penyusunan konstitusi Amerika dari perspektif transisional menambahkan narasi lain terhadap tinjauan yang lazim diterima. Dalam versi idealnya, revolusi Amerika berpuncak dengan penyusunan konstitusi. Konstitusi ini mengandung hal-hal yang bersifat temporer yang berkait dengan revolusi, sekaligus hal-hal yang bersifat permanen.54 Namun, kaitan antara konstitusi Amerika dan revolusi Amerika mencerminkan konstitusionalisme transisional baik dalam proses maupun mandat normatifnya. Terdapat suatu kemajuan bertahap dari konstitusionalisme yang memandang ke belakang menuju konstitusionalisme yang memandang ke depan. Revolusi tidak langsung memuncak pada konstitusi yang fondasionalis, namun menghasilkan sejumlah dokumen yang bersifat konstitutif. Seperangkat perubahan konstitusional yang digerakkan oleh revolusi mendorong diterimanya Konstitusi pada tahun 1787. Rangkaian dokumen konstitutif ini diawali dengan pernyataan justifikasi dalam Deklarasi Kemerdekaan untuk melepaskan diri dari rezim lama. Bahkan, ketika para perintis bangsa bersidang pada tahun 1787, tujuannya adalah untuk mengamendemen traktat konstitutif yang sudah ada.55 Dalam lima tahun pertama setelah revolusi, Articles of Confederation merupakan respon transformatif dan kritis terhadap suatu rezim yang dicirikan oleh kekuasaan negara yang minimal. Meskipun beberapa pakar menyatakan bahwa Konstitusi 1787 menginporporasikan Deklarasi, klaim serupa tidak diterapkan terhadap Articles of Confederation. Namun secara implisit, Konstitusi memiliki kontinuitas dengan Articles of Confederation.56 Suatu skema kekuasaan negara yang lebih ekspansif baru diciptakan setelah disahkannya Konstitusi 1787. Penambahan 54 Untuk tinjauan, lihat Paul W. Kahn, Legitimacy and History: Self-Government in Constitutional Theory, New Haven: Yale University Press, 1992, 58-59 (tentang proses konstitusionalisme yang bergeser dari revolusi ke pemeliharaan). 55 Lihat Richard B. Bernstein, Are We to Be A Nation? The Making of the Constitution, Cambridge: Harvard University Press, 1987, 106. Untuk argumen bahwa kontinuitas antara revolusi Amerika dan Konstitusi Amerika Serikat adalah bagian dari suatu pengalaman politik yang utuh, lihat David A. J. Richards, “Revolution and Constitutionalism in America”, Cardozo Law Review 14 (1993): 577-78. 56 Sebagai contoh, Serikat mengambil alih hutang Konfederasi. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Artikel VI, § 1. 20 Bill of Rights dan amendemen pasca-Perang Saudara ke dalam Konstitusi Amerika menunjukkan tahap-tahap konstitutif berikutnya.57 Dengan sudut pandang ini, sejarah penyusunan Konstitusi Amerika memiliki kemiripan dengan konstitusionalisme transisional. Transisi ini tidak terlalu dramatis, dengan jarak waktu antara Revolusi Amerika dan disahkannya Konstitusi, dan sifat transisi Amerika dari monarki terbatas, bukan dari bentuk kediktatoran yang lebih buruk. Transisi demikian tampak konservatif dibandingkan model lainnya yang dibicarakan di sini; instrumen konstitusional Amerika sendiri mencerminkan hal ini. Bahkan, bisa dianggap terdapat kontinuum transisi dalam hal nuansa dan lingkup perubahan ke arah liberalisme. Dari perspektif transisional, Konstitusi Amerika bukanlah instrumen dasar yang monolitik, namun suatu dokumen yang kontekstual. Penggambaran proses penyusunan Konstitusi Amerika sebagai peletakan dasar secara sadar mengabaikan keberadaan konflik antara para perintis bangsa dan juga tujuan penyusunannya.58 Analisis transisional menunjukkan Konstitusi yang tidak tampak ini, bagian-bagian yang terkait erat dengan kondisi sejarah dan politik masa tersebut. Bahwa provisi-provisi tersebut cenderung diabaikan oleh para pakar kontemporer mungkin disebabkan karena sifatnya yang temporer. Satu ciri utama yang menunjukkan transisionalitas konstitusi Amerika adalah provisinya untuk amendemen.59 Karena proses amendemen sukar dijelaskan dalam model teoretik yang dominan, ia mendorong perdebatan yang panas antara para pakar. Banyak teori konstitusional kontemporer berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana mendamaikan pandangan fondasionalis idealis kontemporer tentang konstitusi yang abadi, dengan perubahan konstitusional, baik yang didasarkan pada proses amendemen Artikel V, melalui prinsip-prinsip interpretasi konstitusional yang berbeda dari pemandangan awal, atau dengan cara-cara lainnya.60 Paradigma yang ditunjukkan dalam bab ini beranggapan bahwa proses amendemen tidak bisa dilihat secara terpisah dari aspek-aspek lain dari perubahan konstitusional. Dalam rangkaian penyusunan Konstitusi Amerika, struktur konstitusional yang mendahuluinya adalah syarat sebelum tercapainya pengakuan terhadap hak-hak individual. Transisionalitas juga menandakan provisi konstitusional tentang hak, yang terutama bersangkutan dengan isu perbudakan yang kontroversial. Konstitusi 1787 menunda semua perubahan tentang peraturan federal tentang perdagangan budak hingga 57 Untuk klaim bahwa terdapat tiga tahapan konstitutif, lihat Ackerman, We the People: Foundations, Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1991, 40, 58. 58 Bandingkan “James Madison to Thomas Jefferson, 4 Februari 1790”, dalam Marvin Meyers (ed.), The Mind of the Founder: Sources of Political Thought of James Madison, edisi revisi, Hannover, N. H: University Press of New England, 1981 untuk Brandeis Uniersity Press: 175-79 (menggambarkan skeptisisme tentang keuntungan perubahan dan revisi konstitusional yang terlalu sering), dengan “Thomas Jefferson to James Madison, 30 January 1787”, dalam Merril D. Peterson (ed.), The Portable Thomas Jefferson, Harmondsworth, Inggris dan New York: Penguin Books, Viking Portable Library, 1977, 415, 417 (menyatakan bahwa “sedikit pemberontakan kadang kala akan menjadi hal yang baik”). 59 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Artikel V (“Kongres, bila dua pertiga dari kedua kamarnya menganggap perlu, akan menyarankan amendemen untuk konstitusi, atau dengan permintaan badan legislatif dari dua per tiga negara-negara bagian, akan bersidang untuk menyarankan amendemen ... ). Tentang rposes amendemen, lihat Sanford Levinson (ed.), Responding to Imperfection: The Theory and Practice of Constitutional Amendment, Princeton: Princeton University Press, 1995. 60 Lihat Akhil Reed Amar, “Philadelphia Revisited: Amending the Constitution Outside Article V”, University of Chicago Law Review 55 (1988): 1044 (mengevaluasi apakah Artikel V merupakan satusatunya sumber perubahan konstitusional). 21 tahun 1898.61 Terlihat bahwa keputusan ini memiliki dua sisi. Ada satu konstitusi untuk saat ini, saat ketika perdebatan politik dibatasi dan solusi federal dipaksakan. Penggunaan redaksi provisional dalam dokumen ini membiarkan kemungkinan penyelesaian prospektif yang lain. Analisis ini didukung oleh pelarangan eksplisit dalam Artikel V terhadap amendemen demikian hingga tahun 1808.62 Dalam kasus yang mungkin paling berpotensi menimbulkan masalah di negara itu, Konstitusi hanya menawarkan prinsip pemandu yang sementara. Suatu perspektif transisional juga menjelaskan pemahaman khas tentang keadilan konstitusional. Perlindungan konstitusi terhadap kebebasan dan konsep tirani yang terkait bisa lebih dipahami dalam konteks pemerintahan kolonial.63 Respon konstitusional yang utama, yang sering kali dianggap sebagai puncak pencapaian dalam Konstitusi, adalah rekonstruksi kekuasaan negara. Bahkan, pembelaan Federalis terhadap skema kekuasaan negara yang baru ini disusun berdasarkan argumen sejarah, berdasarkan pengalaman tirani yang dicirikan oleh kedaulatan parlementer Inggris.64 Respon kritis Konstitusi terhadap pemerintahan monarki adalah definisinya tentang kekuasaan eksekutif; suatu respon yang lebih keras terhadap besarnya kekuasaan eksekutif tampak dalam instrumen konstitusional sementara yang diciptakan setelah Revolusi.65 Hal serupa tampak dalam konstitusi negara-negara bagian, yang membatasi kewenangan dan kekuasaan para gubernur.66 61 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Artikel I, § 9, klausul 1 (“Migrasi atau pengimporan orang-orang demikian seperti dianggap layak oleh negara-negara bagian yang sudah ada, tidak akan dilarang oleh Kongres sebelum tahun seribu delapan ratus delapan ...”). Konstitusi juga memiliki provisi tentang penangkapan dan ekstradisi budak yang melarikan diri. Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Artikel IV, § 2, klausul 3. 62 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Artikel V. 63 Lihat Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic, 1776-1787, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969 (tentang dampak masa pemerintahan kolonial dalam embentuk Serikat). 64 Lihat James Madison, The Federalist, No. 47, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 1961, 301 (“akumulasi semua kekuasaan, legislatif, eksekutif dan judikatif, dalam tangan yang sama, baik seseorang, beberapa atau banyak, dan baik berdasarkan keturunan, penunjukkan diri atau pemilihan, dapat dianggap sebagai definisi tirani itu sendiri”). 65 Pada masa Articles of Confederation (1791), ketidakpercayaan terhadap sentralisasi kekuasaan sedemikian kuat sehingga Kongres tidak dapat menarik pajak dan mengatur perdagangan. Pasal VIII menyatakan: Biaya yang akan dikeluarkan untuk pertahanan atau kesejahteraan bersama, dan diizinkan oleh sidang Kongres Amerika Serikat, akan ditanggung dari perbendaharaan bersama, yang akan ditunjang oleh beberapa negara bagian, sesuai dengan nilai semua tanah dalam masing-masing negara bagian ... Pajak untuk melunasi hal itu akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas dan arahan badan legislatif negara hukum. Pasal IX, selanjutnya, menyatakan: Amerika Serikat dalam sidang Kongres, harus mempunyai hak istimewa dan eksklusif dan kekuasaan atas ... masuk ke dalam perjanjian-perjanjian dan aliansi, dengan syarat bahwa tak ada perjanjian komersial yang akan dibuat dari mana kekuasaan legislatif atas Negara bersangkutan dihalangi atas ... pelarangan terhadap ekspor dan impor dari berbagai jenis barang atau komoditi apa pun .... Untuk argumen yang menganjurkan suatu bacaan atas Konstitusi Amerika dalam perspektif warisan sejarahnya berkenaan dengan Articles of Confederation, kendati tidak sama sekali eksplisit bersifat sebagai 22 Kalau kebanyakan pemerintahan monarkis beralih dari sistem eksekutif yang kuat ke sistem parlementer, maka Amerika Serikat tampak unik dan khas dalam peralihan ke sistem presidensil. Anomali Amerika ini paling baik dijelaskan dalam suatu analisis transisional.67 Justifikasi untuk struktur kekuasaan eksekutif bersandar pada pengalaman historis dari pemerintahan monarkis sebelumnya. Alasan dalam argumen para Federalis untuk kekuasaan eksekutif yang dikedepankan itu didasarkan pada refleksi ke belakang, ke masa pemerintahan raja. Sementara kekuasaan raja tak terbatas, maka kekuasaan presiden dengan masa pemerintahan empat tahun bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Gambaran lain dari kekuasaan presidensil yang dikedepankan itu memiliki justifikasi yang analog: Karena hak veto raja itu bersifat mutlak, maka tidak demikian dengan presiden; presiden mempunyai hak veto yang terbatas dan dipakai seperlunya saja untuk hal yang memang sangat perlu. Pemaparan kekuasaan monarkis dalam sejarah digunakan untuk menjustifikasi atau memperkuat dukungan terhadap ide kekuasaan presidensil dalam hal membuat perjanjian dan kekuasaan menyatakan perang yang terbatas.68 Provisi-provisi Konstitusi yang berkenaan dengan pemerintahan republikan juga menganjurkan suatu fungsi transformatif. Pertama, penyusunan-ulang konstitusi terhadap tatanan politik terjadi melalui redefinisi terhadap partisipasi, keanggotaan, dan kepemimpinan politik. Gambaran anti-aristokratik tampak dalam sejumlah provisi konstitusi, paling jelas tampak dalam pernyataan soal larangan atas “kebangsawanan”. Persyaratan kualifikasi dan jangka waktu bagi partisipasi dan representasi politik memperlihatkan adanya respon yang kritis terhadap tatanan politik yang lama.69 Alokasi kekuasaan militer dan sipil memperlihatkan respon terhadap penyalahgunaan kekuasaan transisional, lihat Akhil Reed Amar, “The Bill of Rights as a Constitution”, Yale Law Journal 100 (1991): 1131. 66 Lihat Daniel A. Farber dan Suzanna Sherry, A History of the American Constitution, New York: West Publishing, 1990, 80-81. 67 Lihat Karl Lowenstein, “The Presidency Outside the United States: A Study in Comparative Political Institutions”, Journal of Politics 11 (1949); 462. 68 Lihat Alexander Hamilton, The Federalist No. 69, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1961, 415-20. 69 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #9, cl 8 (Tak ada gelar kebangsawanan yang boleh diberikan oleh Amerika Serikat: Dan tak satu Orang pun yang memimpin Kantor apa pun atau Perusahaan atau Kartel apa pun di bawah mereka, yang boleh, tanpa Persetujuan dari Kongres, menerima berbagai anugerah, Pengahargaan, Jabatan atau Gelar, dari berbagai jenis apa pun, dari Raja/Ratu/Pangeran siapa pun, atau dari Negara asing”), Pasal I, #10, cl I (“Tak ada Negara yang boleh … memberikan berbagai Gelar Kebangsawanan”); Alexander Hamilton, The Federalist No. 84, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1961, 511-14; Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #2, Pasal II, #1, Pasal III, #1. Lihat juga James Madison, The Federalist Nos.52,53, ed. Clinton Rossiter, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1961, 327-32. 23 oleh rezim militer.70 Suatu perspektif transisional menjelaskan pemahaman kontemporer tentang hak-hak, seperti Amendemen Kedua.71 Suatu gambaran jelas tentang konstitusionalisme transisional ada dalam Rekonstruksi, suatu masa pergolakan tentang bagaimana mentransformasi Serikat. Amendemen Rekonstruksi tampak sangat memandang ke belakang, karena mereka secara normatif membangun struktur status konstitusional pemisahan oleh Konfederasi.72 Amendemen tersebut merespon kejahatan perbudakan dengan menerapkan kewajiban baru terhadap negara-negara bagian selatan; hanya dengan mengakui prinsip kesetaraan di muka hukum, negara-negara bagian tersebut dapat masuk kembali ke dalam Serikat dan direpresentasikan secara setara dalam Kongres.73 Syarat memegang jabatan dalam Amendemen IV mendiskualifikasi para pendukung Konfederasi.74 Pelucutan politik dalam Rekonstruksi tidak berumur panjang; hampir semuanya dicabut oleh Kongres pada tahun 1872.75 Namun, mereka tetap ada dalam teks Konstitusi Amerika sebagai ekspresi abadi politik ekstrakonstitusional. Pemahaman terhadap kaitan transisional antara hukum konstitusional dan politik pasca-Perang Saudara memiliki implikasi mendalam bagi perdebatan kontemporer tentang interpretasi amendemen Rekonstruksi.76 Suatu perspektif transisional dapat mengevaluasi jurisprudensi Rekonstruksi dalam konteks transformasi politik, dengan implikasi bagi kontroversi kontemporer. 70 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Pasal I, #8, cls. 11-16 (yang memberikan kepada Kongres suatu kekuasaan militer yang signifikan), Amendemen II (“Suatu kelompok Milisi yang tertata dengan baik, yang dipandang perlu untuk keamanan sebuah negara yang bebas, hak rakyat untuk menjaga dan mempunyai Angkatan Bersenjata, harus dilarang”), Amendemen III (“Tak boleh ada prajurit yang dalam masa damai ditempatkan di suatu rumah tanpa persetujuan dari sang Pemilik, tidak juga dalam waktu perang, kecuali dengan cara yang ditentukan dan disahkan secara hukum”). 71 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen II; Sanford Levinson, “Comment: The Embarassing Second Amendment”, Yale Law Journal 99 (1989): 648 (mencatat bahwa salah satu dasar Amendemen Kedua adalah “kecemasan terhadap korupsi politik dan tirani oleh pemerintah”). 72 Lihat Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 4 (“Amerika Serikat maupun negara lainnya tidak akan menanggung atau membayar hutang atau kewajiban yang ditimbulkan dari bantuannya terhadap insureksi atau pemberontakan melawan Amerika Serikat ... semua hutang, kewajiban dan klaim demikian akan dianggap ilegal dan tidak sah”). 73 Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, §§ 1-2 74 Amendemen Keempat-belas menyatakan: Tidak seorang pun dapat menjadi Senator atau Wakil dalam Kongres, atau Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, atau memegang jabatan apa pun, sipil atau militer, dalam Amerika Serikat, atau dalam negara-negara bagiannya yang mana pun, yang sebelumnya telah mengambil sumpah, sebagai anggota Kongres, atau sebagai pejabat Amerika Serikat, atau sebagai anggota badan legislatif negara-negara bagiannya yang mana pun, untuk menjunjung Konstitusi Amerika Serikat, [namun] telah melakukan insureksi atau pemberontakan terhadap [Konstitusi] tersebut, atau memberikan bantuan kepada musuh-musuh [Konstitusi]. Namun Kongres bisa, dengan melakukan pemungutan suara yang dispakati dua per tiga dari masing-masing kamar, mencabut pelucutan tersebut. Konstitusi Amerika Serikat, Amendemen XIV, § 3. Bagian ini mulai diberlakukan pada bulan Juli 1868. 75 Lihat Kenneth M. Stampp, The Era of Reconstruction, New York: Knopf, 1970, 170. 76 Bandingkan Raoul Berger, Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, Cambridge: Harvard University Press, 1977, 167 (menyatakan bahwa “para penyusunnya bertujuan untuk melarang diskriminasi dengan memperhatikan privilese tercantum” dan bahwa mereka tidak bertujuan “untuk menjangkau sasaran yang tidak dijelaskan dalam Civil Rights Act dan dikonstitusionalkan dalam amendemen”), dengan Robert J. Kaczorowski, “Revolutionary Constitutionalism in the Era of the Civil War and Reconstruction”, New York University Law Review 61 (1986): 881-903, 910-35 (menjelaskan amendemen dalam konteks teori republikan tentang kewarganegaraan federal dan sifat generik hak-hak asasi). 24 Bab ini telah menunjukkan berbagai cara memahami Konstitusi Amerika Serikat dari perspektif transisional. Dengan menawarkan pandangan yang lebih kontekstual tentang sifat dan peran konstitusionalisme, diskusi di atas melengkapi model yang telah lazim diterima. Konstitusionalisme transisional memiliki implikasi bagi interpretasi konstitusional. Suatu perspektif transisional memberikan pandangan yang unik bagi perdebatan tentang relevansi “tujuan semula” terhadap signifikansi kontemporer berbagai pasal konstitusi yang relevan.77 Perspektif transisional memiliki kemiripan dengan model interpretasi konstitusi “ketaatan” (fidelity) yang menganggap bahwa konstitusi harus diteliti berdasarkan konteks sejarah dan politiknya. Dari perspektif transisional, masalah dengan teori interpretatif kaum originalis ini adalah bahwa mereka biasanya memiliki anggapan tentang suatu tujuan transformatif lain yang bersifat lebih dinamis. Perspektif transisional ini menambahkan pemahaman konstitusi sebagai kodifikasi, yaitu suatu tujuan yang transformatif dan dinamis. Penyelidikan interpretatif yang relevan adalah tentang sejauh mana konstitusi dianggap transisional dan apakah ia bersifat transformatif. Dengan perjalanan waktu, ciri-ciri transisional dari konstitusi akan tampak secara dinamis, baik menghilang atau meluas dalam tujuan transformatifnya. Gabungan dari tujuan-tujuan semula yang mungkin ini memberikan pendekatan yang lebih kontekstual bagi relevansi tujuan semula. Jadi, perspektif transisional menawarkan prinsip yang khas untuk interpretasi konstitusional, dengan konsekuensinya bagi pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Konstitusionalisme Transisional: Beberapa Kesimpulan Teori konstitusional yang lazim diterima tidak cukup untuk menjelaskan fenomena konstitusional yang terkait dengan perubahan politik substansial, terutama pada akhir abad ke-20. Ide-ide utama konstitusionalisme modern adalah respon gaya abad ke-18 terhadap pemerintahan pra-modern dan batasannya terhadap tatanan politik. Namun, konstitusionalisme dalam abad ketiganya bersifat normatif sekaligus transformatif dalam merespon tatanan politik yang sudah ada. Konstitusionalisme demikian menunjukkan dialog antara berbagai modalitasnya: kritis, residual dan restoratif. Dengan demikian, paradigma ini membantu menjawab dilema batas minimal yang diciptakan oleh proses penyusunan konstitusi dalam masa revolusioner. Konstitusionalisme transisional menjembatani perubahan politik radikal dengan mendamaikan dikotomi pemahaman tentang kaitan hukum dan politik. Lebih lanjut lagi, transisi menunjukkan bagaimana 77 Lihat umumnya Berger, Government by Judiciary (membela originalisme); Robert H. Bork, The Tempting of America: The Political Seduction of the Law, New York: Free Press, 1990; Robert H. Bork, “The Constitution, Original Intent and Economic Rights”, San Diego Law Review 23 (1986: 823. Lihat juga Paul Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding”, Boston University Law Review 60 (1980): 204 (mengkritik originalisme); Henry Monaghan, “Our Perfect Constitution”, New York University Law Review 56 (1981): 374-87 (mengkritik Brest); H. Jefferson Powel, “Riles for Originalist”, Virginia Law Review 73 (1987): 659 (menawarkan prinsip-prinsip tentang interpretasi originalis); Mark V. Tushnet, “Following the Rules Laid Down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles”, Harvard Law Review 96 (1983): 786-804 (membantah kemungkinan originalisme tanpa dasar komunitarian). Untuk perspektif tentang originalisme yang menunjukkan relevansinya sebagai dasar, lihat Jed Rubenfeld, “Reading the Constitution as Spoken”, Yale Law Journal 104 (1995): 1119, yang menjelaskan originalisme sebagai model interpretasi “commitmentarian”. Tentang “ketaatan” pada konstitusi, lihat umumnya Larry Lessig, “Fidelity in Translation”, Texas Law Review 71 (1993): 1165. 25 konstitusionalisme memperkuat demokrasi. Pada masa biasa, konstitusionalisme sering tampak bertentangan dengan demokrasi sederhana, namun dalam masa transisi, konstitusionalisme memainkan peran unik dalam memfasilitasi pergeseran menuju rezim yang lebih liberal. Konstitusionalisme transisional memberikan paradigma alternatif. Paradoks utama paradigma ini adalah bahwa seperti dalam konsepsi pra-modern, konstitusionalisme tidak berdiri terpisah dari tatanan politik, namun terkait amat erat dalam politik transformasi. Namun, seperti dalam konsepsi modern, konstitusi transisional juga melampaui tatanan politik biasa. Paradigma transisional ini mengelaborasikan kaitan yang lebih beragam antara politik kontitusional dengan politik biasa: Konstitusi konstitusional tidak saja merupakan kodifikasi konsensus yang sudah ada, namun juga mentransformasi konsensus tersebut. Lebih lanjut lagi, kedua konsepsi tujuan konstitusional ini tidak mutually exclusive; keduanya bisa terdapat dalam satu instrumen. Mereka sering kali terlihat demikian, misalnya dalam Konstitusi Amerika Serikat. Jadi, pandangan yang dikemukakan di sini melengkapi teori konstitusional yang lazim. Yang membedakan paradigma konstitusional transisional adalah kaitan konstruktifnya dengan tatanan politik yang sedang berubah. Konstitusionalisme transisonal mencakup berbagai tahap, dari instrumen sementara untuk membentuk tatanan politik sementara dalam jangka waktu terbatas, hingga hukum yang kukuh untuk memandu identitas politik utama suatu negara. Dalam perannya untuk memutuskan diri dari masa lalu, konstitusi transisional meratifikasi tatanan politik baru untuk meliberalisasi ruang politik, memungkinkan tatanan yang lebih liberal. Konstitusionalisme transisional bervariasi dari watak sementara hingga amat kukuh, bertugas untuk memelihara tatanan konstitusional di masa depan. Paradigma konstitusional transisional menjelaskan kontribusi khusus penyusunan konstitusi dalam masa-masa perubahan politik. Dengan mengabaikan kecenderungan umum untuk menggabungkan konstitusionalisme dengan perubahan politik radikal, paradigma yang dikemukakan di sini memberikan ruang dan bahasa untuk mengkritik sifat dan peran konstitusionalisme dalam masa transformasi. Paradigma konstitusionalisme transisional juga memiliki implikasi bagi pemahaman tentang kekuatan normatif konstitusionalisme dan kaitannya dengan penggunaan lain dari hukum. Konstitusionalisme kritis merupakan respon transformatif yang eksplisit terhadap pemerintahan represif di masa lalu. Dengan memberikan respon kritis terhadap rezim lama ini, konstitusionalisme transisional memberikan suatu rasa keadilan. Respon konstitusional kritis terhadap rezim politik pendahulu ini memberikan justifikasi bagi transisi dengan mendelegitimasi berbagai aspek rezim lama dan melegitimasi rezim penggantinya. Dengan memberikan ekspresi pertanggungjawaban secara normatif, konstitusionalisme bertumpang tindih dengan hukum-hukum normatif lainnya, seperti hukum pidana, dalam masa-masa luar biasa tersebut. Norma-norma konstitusional postmodern-kontemporer melampaui struktur kekuasaan negara untuk memandu pemahaman normatif yang lebih luas terhadap tatanan sosial. Akhirnya, perspektif konstitusional transisional memberikan gambaran kemajuan konstitusional. Pandangan tentang kemajuan ini tidak bersifat mutlak atau universal, tetapi terbatas dan kontekstual. Pemahaan terhadap sejarah ketidakadilan di masing-masing negara memungkinkan konstruksi batasan konstitusional yang benar-benar responsif terhadap peninggalan politik, historis dan konstitusional suatu negara. 26 Bab 7 Menuju Teori Keadilan Transisional Buku ini telah mengeksplorasi dua pertanyaan: pertama, pendekatan legal apa yang diadopsi oleh masyarakat yang sedang mengalami masa transisi sebagai respon terhadap warisan penindasannya?; kedua, apa signifikansi dari respon-respon legal ini terhadap prospek liberalisasi masyarakat tersebut? Kita sekarang berada pada posisi untuk menguji cahaya apa yang dipancarkan oleh buku Transitional Justice ini di atas kedua pertanyaan tersebut dan, lebih umum lagi, terhadap peranan hukum dalam periodeperiode yang masih sangat jauh dari pencapaian perubahan politik. Dalam mengeksplorasi respon-respon legal negara terhadap warisan keterkungkungannya, Transitional Justice menawarkan metode interpretatif, historis, dan komparatif untuk menarik konklusi sintetik berkenaan dengan apa yang dikedepankan oleh praktik-praktik ini tentang konsepsi keadilan pada masa-masa seperti itu. Apa yang mencuat adalah suatu penyeimbangan pragmatik tentang keadilan ideal dengan realisme politik yang mencontohkan kedaulatan hukum simbolis yang mampu mengkonstruksikan perubahan yang menghasilkan liberalisasi. Dengan demikian, bab ini, yang merupakan penyimpulan dari keseluruhan uraian kita di depan, menganalisis fenomena legal yang dibahas dalam keseluruhan buku ini. Yaitu, fenomena legal yang menyangkut teori tentang keadilan transisional yang menjembatani konsep ideal tentang kedaulatan hukum dan kebutuhan mendesak akan politik kontingen dalam kasus-kasus tertentu. Pertimbangan-pertimbangan hukum selama periode semacam ini mengikuti suatu paradigma yang khas, yang diarahkan oleh prinsip-prinsip kedaulatan hukum yang disesuaikan dengan tujuan transformasi politik. Analisis yang diambil di dalam buku ini memperlihatkan saluran konseptual dan praktis yang melaluinya paradigma paling khusus dalam hukum transformatif membantu membangun perubahan yang mengarah pada liberalisasi. Tetapi, analisis kita melaju lebih jauh lagi. Analisis kita di sini mengajukan bahwa hukum memantapkan potensi pemerdekaan bagi dihasilkannya politik transformatif. Beragam respon legal yang digali di dalam bab-bab sebelumnya mengungkapkan gambaran umum dalam soal hakikat dan fungsinya – dan dengan demikian, mengungkapkan juga hasil-hasil yang mempersulit bagi konsepsi koheren secara analitik tentang keadilan transisional yang melampaui kasus-kasus khusus. Prinsip-prinsip kedaulatan hukum paradigmatik dalam keadilan transisional dihubungkan secara dekat pada gambaran murni dan penjelas dari periode ini, yaitu pendasaran dalam masyarakat bagi penggantian normatif dalam prinsip yang menyertai dan melegitimasi pemberlakuan kekuasaan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan transisional yang dikembangkan di sini seharusnya sudah jauh melebihi periode-periode perkembangan politik biasa, yang memancarkan cahaya baru ke atas pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang menyangkut hukum-hukum hak asasi manusia yang potensial bagi pemberian respon terhadap konflik-konflik internasional, dan pemahaman inti tentang kesulitan-kesulitan hubungan politik dengan keadilan. 1 Eksplorasi buku ini terhadap hakikat dan fungsi hukum dalam periode transformasi yang dimulai dengan penggantian konsep debat dan kerangka acuan yang relevan, bagi keadilan transisional tidak cukup ditangkap secara memadai dalam konsep analitik yang biasa berlaku yang digunakan untuk menguji peranan hukum dalam periode-periode perubahan politik yang membawa pembebasan. Pertimbanganpertimbagan ini cenderung menjadi sangat antinomik atau kontradiktif. Pertimbanganpertimbangan tersebut bisa secara radikal bersifat realis, dengan serangkaian pengembangan dalam transisi yang sekadar mengikuti keseimbangan kekuasaan (dan dengan demikian mengingkari keterkaitan hukum dengan signifikansi independen dalam transformasi politik), atau menawarkan narasi-narasi yang diidealkan di mana hukum beroperasi sebagai keseluruhan kekuatan pemicu yang mendasar dan berlaku dari dirinya sendiri, yang memprasyaratkan serangkaian pembangunan hukum dan politik yang berpotensi universal selama periode-periode transformatif.1 Tak satu pun dari pemahaman yang sangat dikotomis ini menyediakan penjelasan positif yang persuasif atau penjelasan normatif tentang peran hukum dalam periode-periode perubahan politik substansial. Dengan mendasarkan pada gambaran perspektif historis dan komparatif lintas masyarakat, analisis yang kita kemukakan di sini mengajukan sebuah cara alternatif untuk mengkonseptualisasikan peran hukum dalam masa-masa seperti itu. Pertimbangkanlah, sebagai langkah awal, konseptualisasi implisit karya-karya para sarjana yang akrab di benak kita selama ini tentang masalah yang relevan: peran hukum hanya sekadar direduksi pada keseimbangan kekuatan politik yang membentuk permulaan perubahan rezim atau diekstrapolasi dari titik akhir di mana “revolusi liberal” diyakini akan tercapai.2 Hasilnya, peran hukum dalam periode yang menyita perhatian itu – dimengerti sebagai konteks politik untuk menunjukkan interregnum, yaitu masa antara dua rezim pemerintahan3 – telah menghindari pemahaman, karena masing-masing dari pendekatan ini menurut definisi menampik fenomenologi hukum dalam liberalisasi sebagai subjek analisis yang diskret atau benar-benar terpisah. Analisis ini sama sekali tidak menolak atau meminimalisir pentingnya pembatasan struktural dan tujuan-tujuan normatif dalam pembentukan proses legal dan hasil-hasil politik. Sebaliknya, fenomena hukum jelas-jelas tidak pernah bersifat otonom terhadap konteksnya, tidak juga benar-benar responsif terhadapnya. Kemudian, mengapa gerangan ada alasan untuk berasumsi, sebagaimana dilakukan oleh masing-masing pendekatan yang berlaku sekarang ini, bahwa operasi hukum kurang interaktif dan dialektis selama periode-periode perubahan politik yang masih jauh panggang dari api? Sesungguhnya, sebuah analisis sistematik proses hukum yang terjadi selama perjalanan dari satu rezim politik ke rezim politik lainnya adalah benar-benar apa yang diperlukan Bandingkan Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, 215, dengan Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992, dan Hannah Arendt, On Revolution, Wesport, Conn.: Greenwood Press, 1963. 2 Ibid. 3 Untuk definisi transisi dalam ilmu politik, lihat Guillermo O’Donnel dan Phillippe C. Schmitter, Transitions From Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 6. 1 2 dalam rangka mengklarifikasi hakikat dan cakupan peran mereka dalam periode transisional. Lebih dari sekadar hasil-hasil penggambaran kita sebagai residu semata dari keseimbangan kekuatan politik atau deduksi respon-respon legal ideal dari titik akhir yang revolusioner yang mempraandaikan adanya demokrasi dan kedaulatan hukum, perlulah bagi kita untuk menguji relasi respon legal transisional terhadap warisan sejarah masyarakat atas ketidakadilan dan cakupan yang terhadapnya relasi ini membentuk lorongnya sendiri menuju liberalisasi. Kegunaan dari pendekatan ini akan menjadi lebih jelas ketika kita kembali pada pembahasan tentang fenomenologi legal dan prinsipprinsip kedaulatan hukum yang dapat diterapkan yang merupakan karakteristik dari contoh-contoh kontemporer tentang transformasi politik radikal. Keadilan Transisional dan Jurisprudensi Transisional: Sebuah Paradigma Hukum dalam periode perubahan radikal umumnya dipahami sebagai antistruktural, sebagai prinsip yang melampaui kenyataan dan paradigma yang menantang.4 Periode perubahan normatif umumnya dilihat menjadi antiparadigmatik. Tetapi, fenomenologi legal yang mencirikan periode perubahan politik mengungkapkan pola-pola yang menunjukkan sebuah paradigma. Sebagaimana telah kita lihat, manifestasi keadilan yang diupayakan selama periode transformatif sangat beragam: retributif, reparatoris, birokratis, konstitusional, dan historis. Akan tetapi, melampaui berbagai respon legal yang beragam, pengaturan menjadi bukti, yang mengungkapkan proses-proses distingtif yang dipadukan dengan perubahan politik. Melampaui kategori-kategori legal, sebuah paradigma hukum muncul yaitu paradigma jurisprudensi transisional. Karena gambaran yang mendefinisikan transisi adalah perubahan normatif transisi itu sendiri, praktik-praktik hukum menjembatani suatu perjuangan yang persisten di antara dua titik: dukungan terhadap konvensi yang mapan dan transformasi yang radikal. Utamanya, suatu posisi yang dipengaruhi secara dialektis kemudian muncul. Dalam konteks perubahan radikal politik, jurisprudensi transisional mendamaikan konsepsi parsial dan non-ideal tentang keadilan: bentuk-bentuk sementara dan terbatas dari konstitusi, sanksi, reparasi, pemurnian [pemulihan nama baik], dan sejarah. Melampaui kategori-kategori hukum, bentuk legal yang distingtif menengahi gerakan di antara rezim-rezim yang sudah dan sedang berkuasa. Peran hukum di sini bersifat transisional, dan tidak mendasar, konstruktif terhadap perubahan-perubahan kritis dalam status, hak, dan tanggung jawab individual – dan, lebih luas lagi, terhadap pergantian dalam hubungan kekuasaan. Sebagaimana peran hukum adalah untuk memajukan konstruksi perubahan politik, manifestasi hukum transisional dipengaruhi secara lebih tegas lagi oleh nilai-nilai politis dalam rezim di masa transisi daripada manifestasi hukum dalam negara-negara di mana kedaulatan hukum telah ditegakkan Lihat Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press, 1970, 52-76, 111-134. Untuk argumen yang menentang paradigma konseptualisasi, lihat Albert Hirschman, “The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding”, dalam Paul Rabinow dan William M. Sullivan (eds.), Interpretive Social Science: A Second Look, Berkley: University of California Press, 1987. 4 3 dengan kokoh. Jadi, jurisprudensi periode-periode ini tidak mengikuti prinsip-prinsip utama soal legalitas sebagai keteraturan, kelaziman, dan prospektivitas [keterarahan pada masa depan] – hal-hal yang merupakan esensi paling inti dari kedaulatan hukum dalam masa-masa biasa.5 Sementara kedaulatan hukum dalam demokrasi-demokrasi yang mapan senantiasa menatap ke depan dan terus tiada henti berjalan pada alur arahnya yang sudah pasti, hukum dalam periode transisional justru menatap ke belakang sembari juga menatap ke depan, restrospektif dan sekaligus prospektif, berkesinambungan dan sekaligus terputus-putus. Biasanya, nilai-nilai prospektivitas dan kontinuitas, juga keterterapan secara umum dan perlindungan yang sama dan adil, dirasakan menjadi sangat kompatibel dalam sistem hukum yang mapan. Akan tetapi, dalam periode-periode perubahan politik secara substansial, nilai-nila ini justru tampak jelas terjerembab dalam konflik. Ini paling jelas manifes baik dalam periode langsung pasca-perang dan yang mengikuti kejatuhan Komunisme dalam perdebatan jurisprudensial menyangkut hubungan hukum dan moral dan menyangkut makna restorasi kedaulatan hukum. Perjuangan melampaui cakupan yang terhadapnya prosedur yang telah ada sebelumnya diarahkan pada atau nilai-nilai rezim yang baru dikembangkan. Nilai-nilai kedaulatan hukum mana yang terutama muncul pertama dalam transisi adalah fungsi dari warisan sejarah dan politik tertentu – yaitu, fungsi dari pemahaman utama terhadap sumber-sumber ketakutan, ketidakamanan, dan ketidakadilan yang mendapatkan kekuatan normatif otoritatif dalam masyarakat. Sementara keseimbangan kekuasaan di antara aktor-aktor politik kunci bisa dipandang sebagai pembatasan rentang kemungkinan, tantangan yang paling besar dan peran distingtif jurisprudensi transisional, bagaimanapun juga, tetaplah menjembatani legalitas konvensional dan pergantian normatif yang diprasyaratkan oleh transformasi yang membawa pembebasan. Dalam periode perubahan politik, tak ada kawasan tunggal bagi tindakan hukum yang operatif, dan tak ada pula ideal-ideal mendasar yang tak menunjukkan kekhasan antara satu dengan lainnya. Namun demikian, pengalaman-pengalaman transisional tidak perlu mengikuti wacana yang telah dipostulasi oleh realis politik berdasarkan basis pertimbangan keseimbangan kekuasaan. Alih-alih, pertanyaan yang benar-benar menghujam adalah: Institusi apa yang memiliki legitimasi untuk menjalankan transformasi normatif yang substansial? Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, peran reinterpretasi makna kedaulatan hukum dalam periode-periode transformasi substansial sering kali ditangani oleh pengadilan-pengadilan konstitusional, khususnya ketika institusi-institusi tersebut merupakan institusi yang sama sekali baru yang dimunculkan oleh transisi itu sendiri. Sistem judisiari transisional mempraktikkan kebebasan interpretatif yang masuk akal dan wajar, mengukir kedaulatan hukum yang tak jauh beda yang secara simultan mendukung aspek-aspek legalitas konvensional sembari melakukan kerja perubahan normatif. Jadi, ajudikasi dalam periode-periode ini hampir selalu mengungkapkan suatu kombinasi dinamis dari imperatif-imperatif konvensional dan transformatif. Kendati bukan merupakan tindakan dari badan-badan pembuat keputusan politik, namun respon-respon ajudikatoris tersebut menjadi simbol5 Lihat Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven: Yale University Press, 1964. 4 simbol signifikan dari pembebasan kedaulatan hukum. Ketika pengadilan-pengadilan konstitusional mendahului transisi, institusi-institusi lain yang dirasuki dengan legitimasi dan otoritas yang baru ditemukan, seperti komisi-komisi publik, menjadi ajang bagi praktik-paraktik transformatif. Pada saat yang sama, transisi bervariasi dalam perluasannya terhadap transformasi normatif dan dalam kepatuhan terhadap legalitas konvensional. Dengan demikian, sebuah teori tentang keadilan transisional harus mengembangkan sebuah bahasan yang dengannya kita memahami kontinum transformatif yang bersamanya transisi ditata. Modalitas yang mungkin merentang mulai dari modalitas “kritis”, yang mengacu pada reportoire hukum transformatif yang ditujukan secara maksimal pada penolakan kebijakan rezim sebelumnya, hingga pada modalitas “residual”, yang bertujuan memantapkan tatanan hukum yang sedang berlaku sekarang. Sebaliknya, modalitas “restoratif” menarik kekuatan normatif dari keberpulangan pada warisan negara di masa lalu. Sebagaimana disarankan oleh tipologi ini, modalitas yang bervariasi berhubungan dengan perbedaan-perbedaan dalam cakupan transformasi politik yang baru, kendatipun tidak harus dalam cakupan liberalisasi, khususnya ketika sebuah reportoire “restoratif” bisa secara meyakinkan memanfaatkan atau berdiri tegak di atas tradisi yang tepat, yang telah hidup sebelumnya. Sebagaimana yang hendak ditunjukkan oleh pembahasan kita dalam bab-bab sebelumnya, prinsip kedaulatan-hukum yang dipadukan dengan modalitas transformasi merupakan bukti yang melintasi kategori-kategori hukum. Sebenarnya, kita bisa melanjutkan pembahasan tentang hal ini kemudian. Sebaliknya, prinsip kedaulatan hukum yang dipadukan dengan waktu biasa mencakupi distingsi yang jelas dalam kategori hukum yang berkenaan dengan aturan prosedural dan aturan pembuktian, dan juga pembatasan status individual, hak dan kewajiban, sifat luar biasa dan kerja-kerja dari hukum transisional yang sering kali mengaburkan tapal batas yang memisahkan hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif [~ hukum administrasi negara] dan hukum konstitusional [~ hukum tata negara]. Dalam pelaksanaan kategori-kategori hukum, prinsip kedaulatan hukum transisional yang paradigmatik bisa juga cenderung memecahkan pagar batas konvensional ini di dalam hukum. Sebagai contoh, pengembangan kedaulatan hukum di dalam negara yang sedang melakukan proses liberalisasi sering dianggap bergantung pada penerapan akuntabilitas individual. Jadi, penghukuman sering jelas-jelas mencontohkan kepedulian terhadap tanggung jawab individual yang merupakan hal sentral dalam hukum di negara-negara liberal. Akan tetapi, sebagaimana telah ditunjukkan dalam bab 2, perspektif yang menekankan pada hakikat penghukuman ini tidak sesuai dengan perannya dalam waktuwaktu terjadinya pergolakan dan perubahan politik secara radikal. Konsep pidana atau rumusan kejahatan masa transisional malah ganti ditentukan oleh nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda dan proyek proses perjalanan politik. Keadilan pidana biasanya diteorisasikan dalam konsep-konsep yang sangat dikotomis sebagaimana dihidupkan dalam kepedulian yang berorientasi kepada masa lalu dengan retribusinya atau yang berorientasi ke masa depan, sebuah kepedulian utilitarian dengan penekanan pada efek penjeraan, yang dianggap sebagai bagian internal 5 dari sistem keadilan.6 Akan tetapi, dalam varian transisional ini bukan cuma penghukuman yang dijelaskan dengan suatu campuran dari tujuan retrospektif dan prospektif, tetapi juga pertanyaan soal entahkah menghukum atau mengampuni dirasionalisasikan secara sengaja dan terbuka dalam konteks politik. Nilai-nilai kerahiman dan rekonsiliasi yang umumnya dipandang sebagai hal-hal di luar keadilan kriminal merupakan bagian eksplisit dari pemahaman konsep transisional. Politisasi eksplisit dari hukum pidana di dalam periode-periode ini menantang pemahaman ideal tentang keadilan dan kemudian hadir menjadi gambaran yang persisten atau tetap tak berubah-ubah dari jurisprudensi di dalam konteks transisional. Rumusan atau bentuk transisional yang luar biasa dari penghukuman yang ditentukan ciri khasnya dalam bab 2 sebagai sanski pidana “terbatas” kurang diarahkan pada penjatuhan hukuman kepada para pelaku; malahan lebih diarahkan pada peningkatan upaya pergantian normatif transformasi politik. Sanksi terbatas transisional dicontohkan di mana pun proses pidana bersifat parsial dan sepotong-sepotong, selain itu, sanksi tersebut juga terutama memuncak pada hukuman yang ringan atau tanpa hukuman sama sekali. Sanksi terbatas juga diilustrasikan secara historis, bukan cuma dalam kebijakan pasca-perang, tetapi juga dalam masalah penghukuman yang mengikuti kasus-kasus terbaru dari perubahan rezim, yang selama terjadinya perubahan itu sanksi tebatas tersebut menjalankan tindakan-tindakan operatif yang penting – penyelidikan publik formal ke dalam klarifikasi masa lalu, penuntutan terhadap kesalahan masa lalu, dan seterusnya – yang menyokong pergantian normatif yang merupakan hal sentral terhadap liberalisasi transisi. Bahkan bentuknya yang terbatas dan menggelikan adalah suatu simbol kedaulatan hukum yang memampukan ekspresi pesan normatif kritis. Berkenaan dengan argumen yang dibahas lebih jauh di sini, sangatlah penting untuk memperhatikan afinitas bahwa efek-efek operatif yang dikembangkan lebih lanjut oleh sanksi pidana yang terbatas, semisal menetapkan, mencatat, dan menghukum kesalahan masa lalu, tampil bersama tindakan-tindakan hukum lainnya dan prosesproses yang yang konstruktif terhadap transisi. Kesalahan yang masif dan sistemik yang secara khusus dicirikan oleh represi modern menganjurkan adanya suatu pengakuan akan campuran tanggung jawab individual dan kolektif. Dengan begitu, ada ketumpangtindihan yang jelas antara institusi-institusi dan prose-proses punitif dan administratif. Proses-proses akuntabilitas yang diindividualisasikan memberikan jalan kepada investigasi administratif dan komisi penyelidikan, kompilasi rekaman-rekaman publik, dan pemberitahuan resmi tentang kesalahan masa lalu tersebut. Sering kali, semuanya ini adalah kesalahan-kesalahan yang tercakup dalam sejarah kenegaraan yang dilakukan mengikuti mandat politik bagi rekonsiliasi, seperti di Afrika Selatan dan di kebanyakan negara Amerika Latin pasca-otoritarian.7 Apakah bentuk-bentuk birokratis dari penyelidikan publik dan penutur-kisahan kebenaran secara resmi merupakan hal yang diinginkan dan apakah itu juga menandakan Lihat H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford: Clarendon Press, 1968. Lihat juga George Fletcher, Rethinking Criminal Law, Boston: Little, Brown, 1978 7 Berkenaan dengan Afrika Selatan, lihat Kader Asmal, Louise Asmal, dan Ronald Suresh Roberts, Reconciliation Through Truth: A Reckoning of Apartheid’s Criminal Governance, Cape Town, S. Africa: David Philip Publishers bekerja-sama dengan Mayibue Books, University of Western Cape, 1996. 6 6 liberalisasi, keduanya itu merupakan hal yang kontingen atau tergantung pada warisan negara dari aturan yang represif. Peran produksi pengetahuan sosial yang berkenaan dengan masa lalu sebuah negara bukan merupakan suatu masalah orisinal atau masalah mendasar, karena fungsi kritis rezim kebenaran suksesor adalah untuk merespon praktikpraktik represif dari rezim terdahulu. Jadi, sebagai contoh, dalam transisi setelah pemerintahan militer, ketika kebenaran merupakan korban dari kebijakan-kebijakan penghilangan,8 respon-respon kritis merupakan upaya pelacakan terpadu dari suatu kisah resmi dan rahasia, sementara sebaliknya, sejarah negara telah dihindarkan secara luas dalam transisi pasca-komunis, ketika produksinya tidak lebih merupakan sebuah instrumen kontrol represif semata. Penyelidikan historis transisional mengungkapkan bahwa kebenaran yang relevan adalah kebenaran yang dihasilkan di dalam warisan negara yang khusus dalam hal ketidakadilan. Kebenaran-kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang tidak universal, tidak esensial dan kebenaran yang tergolong dalam meta-kebenaran (metatruth). Sebagaimana ditunjukkan dengan penggunaan transisional yang digeneralisasikan dari pertimbangan independen dalam hukum hak asasi manusia kontemporer untuk menyingkirkan rezim kebenaran predesesor (rezim pendahulu) dan menegakkan sebuah konsep primer pertanggungjawaban, kebenaran marjinal bisa jadi adalah kebenaran yang dibutuhkan untuk mematrikan sebuah garis batas antara rezim baru dan rezim lama tersebut.9 Penjelasan historis yang baru tentang warisan masa lalu merehabilitasi, juga menghukum, individu-individu tertentu. Dalam bentuk transisionalnya, upaya hukum reparatoris memainkan peran penting dalam pergantian normatif dengan mencontohkan perubahan-perubahan yang berkenaan dengan status politik, sebagai misal, rehabilitasi dan restorasi martabat individual yang dipadukan dengan liberalisme, yang bisa menyertai upaya hukum lainnya dalam hal yang bersifat distributif. Melintasi keragaman budaya, tuntutan terhadap pertimbangan-pertimbangan reparatoris sebagai tampilan dari perlindungan yang sama di bawah hukum merupakan perubahan yang pervasif atau menyebar ke segala arah, perubahan yang melaju laksana sepur dalam aturan yang berkaitan dengan status individual dan hak. Dalam teori ideal, prinsip-prinsip keadilan korektif umumnya berorientasi atau melihat ke belakang, yang terutama berkaitan dengan hak-hak korban individual. Akan tetapi, dalam bentuk transisionalnya, pertimbangan reparatoris memiliki suatu hakikat “hibrida”, dengan tujuan-tujuan korektif yang dikaitkan dengan kepedulian sosial yang lebih luas yang dihubungkan dengan perlindungan normatif dari perubahan politik yang membebaskan. Kombinasi hibrida proyek reparatoris transisional dari tujuan-tujuan berorientasi ke belakang dan tujuan-tujuan berorientasi ke depan adalah bukti paling nyata di negara-negara yang sedang melalui tahap transisi simultan dalam bidang ekonomi dan politik, yang keluar secara radikal dari penteorisasian ideal tentang prinsip-prinsip keadilan distributif dan keadilan korektif.10 8 Untuk diskusi lebih mendalam dan lebih luas tentang poin ini lihat bab 3, “Keadilan Historis”. Lihat Nunca Más: Report of the Argentine National Commission on the Disappeared, edisi bahasa Inggris, New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986 (yang untuk selanjutnya disebut Nunca Más saja). 10 Untuk pembimbing elaborasi semacam itu dalam teori ideal, lihat John Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993. 9 7 Kompromi transisional tidak lain adalah yang paling jelas sebagaimana dalam transisi pasca-komunis, ketika bahkan yang sering disebut-sebut sebagai “hak milik” tidak disusun di atas dasar-dasar pemikiran ideal.11 Upaya hukum reparatoris transisional meneruskan dan menekankan “hak atas sesuatu” yang berupaya mengkoreksi pelanggaran terhadap hak di masa lalu secara tepat supaya menyelimuti dan memelihara hak-hak itu secara simultan di masa depan. Sekali lagi, melalui proyek-proyek legislatif yang luas, sering kali diperluas atau diamendemen oleh institusi judisial, negara yang sedang mengupayakan pembebasannya menerima suatu bentuk perbaikan yang sistemik untuk pengingkaran masa lalu yang sistemik dari perlindungan hukum yang sama. Dalam bentuk birokratiknya, dasar-dasar politis dan kolektif pengukuran transisional adalah yang paling diinginkan dan terbuka, hukum berada pada keadaan transformatifnya yang paling radikal, dan batas-batas yang memisahkan kategori hukum menjadi paling kabur. Tindakan-tindakan regulatoris publik yang menguatkan asosiasi, keanggotaan, dan partisipasi menghasilkan perubahan yang real dalam status, hak, dan kewajiban para warga dalam rezim yang baru dan, oleh karena itu, bisa memiliki dampak yang radikal dan menyebar luas pada tatanan politik negara.12 Untuk pastinya, keadilan administratif transisional mengandung bentuk-bentuk atau konsep hukum konvensional, yang sekali lagi mendemonstrasikan kompromi transisional. Akan tetapi, dengan bersandar pada perilaku masa lalu sebagai basis bagi tindakan prospektif dalam ranah publik, maka penilaian atau pengukuran ini menampilkan aspek punitif dari hukum pidana. Ketika hukum publik dikembangkan di atas dasar yang eksplisit dari kondisionalitas politik, maka hukum tersebut secara kritis merespon warisan penganiayaan yang dilakukan di atas dasar-dasar klaim ideologis, yang secara radikal membentuk ulang batas-batas legitimasi politik dan dengan demikian meredefinisi raut wajah (kontur) identitas politik yang berubah dari masyarakat suksesornya. Sebenarnya, dalam pengembangan perilaku di masa depan berdasarkan pada klaim-klaim politis, berbagai pertimbangan atau penilaian ini juga tampak menjadi sangat konstitusional sifatnya. Konstitusionalisme transisional juga tidak mengikuti konsepsi ideal13 tetapi ia bersifat hiperpolitisasi, yang menampilkan afinitas dengan respon-respn transisional lainnya. Intuisi kita adalah untuk menggambarkan konstitusi yang membuatnya sebagai proyek yang seluruhnya melihat ke depan yang didesain untuk membentuk atau mendirikan pemerintahan masa depan. Tetapi, konstitusionalisme transisional memiliki fungsi tambahan yang dirangkaikan dengan penggantian normatif, sebagaimana halnya, pada saat yang bersamaan, ia mengarah ke belakang dan sekaligus ke depan, retrospektif dan sekaligus prospektif, dan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan dengan tatanan politik sebelumnya. Yang juga termasuk dalam wilayah hukum ini yaitu bahwa kontinum transformatif, yang merentang dari yang “kritis” ke yang “residual” dalam kaitannya dengan dukungan atau kepatuhan terhadap status quo, merupakan bukti paling nyata. Konstitusi transisional yang membuat pencakupan tujuan-tujuan 11 Untuk diskusi lebih lanjut dan lebih dalam, lihat bab 4, “Keadilan Reparatoris”. Lihat bab 5, “Keadilan Administratif”. 13 Lihat misalnya, Ackerman, Future of Liberal Revolution. 12 8 pengkodifikasian, tujuan-tujuan perlindungan, yang diasosiasikan dengan konstitusionalisme dan juga transformatif, tujuan-tujuan pembiaran yang unik pada masa transisi. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini, konstitusi transisional bisa secara keseluruhan bersifat sementara, yang dimaksudkan untuk beroperasi hanya untuk jangka waktu tertentu selama adanya perubahan yang didorong itu, sebagaimana dicontohkan dalam Konstitusi sementara Afrika Selatan 1993, atau tujuan yang secara langsung untuk konstruksi yang melindungi secara ketat, konstruksi yang tak bisa diganggu gugat dan diubah-ubah dari identitas politik yang permanen, sebagaimana dalam kasus Grundgesetz pasca-perang Jerman.14 Afinitas paradigmatik yang didiskusikan di sini lahir di atas pertanyaan yang kembali mencuat dalam perdebatan yang mengitari keadilan transisional, yang berkenaan dengan respon terhadap aturan represif yang paling tepat untuk ditempatkan dalam sistem demokratik yang permanen. Subteks dari pertanyaan ini mengandaikan adanya ideal transisional dan bahwa permasalahan normatif agaknya mempengaruhi suatu respon kategoris tertentu. Akan tetapi, ini hanyalah sekadar sebuah pertanyaan yang salah: Tak ada respon benar yang tunggal terhadap masa lalu yang represif dari sebuah negara. Respon mana yang tepat dalam berbagai rezim yang ada dalam konteks transisi bersifat kontingen atau tergantung pada sejumlah faktor – warisan ketidakadilan masyarakat, kultur hukumnya, dan tradisi-tradisi politiknya – termasuk juga tergantung pada eksigensi atau urgensi tuntutan-tuntutan politik transisionalnya. Sebenarnya, jauh melampaui ketergantungan respon-respon, muncul ketidakrelevanan yang umum dari beberapanya yang bersifat khas yang kemudian diadopsi. Fluiditas atau keteraliran paradigmatik dari respon-respon hukum transisional menekankan karakter politik yang semakin meningkat dari jurisprudensi ini.15 Untuk fungsi hukum dalam periode-periode ini, sifatnya sangatlah simbolis, sehingga respon-respon berganda dan beragam bisa dan sungguh-sungguh memediasi pergantian normatif. Mari kita sekarang mempertimbangkan secara lebih detail lagi bagaimana paradigma keadilan yang didiskusikan di sini bersifat konstruktif terhadap pergantian atau pengalihan ini. Konstruktivisme Transisional Bagaimana transisi dikonstruksikan? Apa peran hukum dalam proses perjalanan politik seperti itu? Pertanyaan tentang peran konstruktif hukum secara umum muncul dalam konteks problem produksi sosial yang lebih konvensional dan transmisi norma-norma otoritatif melintasi waktu. Sesungguhnya, problem reproduksi institusional dan pertanyaan-pertanyaan terkait soal legitimasi telah distudi dengan baik.16 Akan tetapi, Lihat Basic Law for the Federal Republic of Germany, Pasal 79 (perlindungan terhadap gambaran demokratik yang utama bertentangan dengan provisionalitas atau kesementaraannya yang diperkirakan). 15 Bandingkan dengan Carl Smith, The Concept of the Political, terj. George Schwab, Chicago dan London: University of Chicago Press, 1996, 31 n12. 16 Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Anchor Books, 1966, 86. Lihat juga Paul Connerton, How Societies Remember, New York: Cambridge University Press, 1989. Tentang konstruksi di dalam hukum, lihat 14 9 perubahan politik dan sosial yang mendasar melibatkan pergantian di dalam tatanan normatif yang mengekspresikan penteorisasian yang tidak lumrah, karena penggeneralisasian sistem hukum yang mapan dan politik tidak menyentuh apa yang khusus dalam peran hukum pada periode-periode semacam itu.17 Lebih dari sekadar bagaimana hukum membentuk suatu sistem yang mampu memproduksi norma-norma pelegitimasian yang ada sekarang ini, problemnya itu sendiri adalah bagaimana normanorma tersebut secara radikal ditransformasikan di dalam dan melalui hukum. Watak paradigmatik hukum yang mencuat dalam masa-masa ini beroperasi dalam model yang luar biasa dan melahirkan suatu relasi yang konstruktif terhadap transisi. Ia menstabilisasikan sekaligus men-de-stabilisasikan. Dalam keadaan-keadaan ini, gambaran distingtif hukum merupakan fungsi mediasinya, sebagaimana ia mengukuhkan level ambang batas kontinuitas formal sembari mencontohkan diskontinuitas transformatif. Perluasan yang terhadapnya kontinuitas formal akan dimantapkan sangat tergantung pada modalitas transformasi sebagaimana dipaparkan di atas, sembari muatan nilai pergantian normatif akan menjadi sebuah fungsi sejarah, kultur, dan tradisi politik, termasuk juga keberterimaan masyarakat terhadap inovasi. Apa sajakah yang dimiliki praktik-praktik hukum transisional secara umum? Hukum juga mengkonstruksikan sejumlah proses yang beraneka ragam, termasuk legislasi, ajudikasi, dan pertimbangan-pertimbangan administratif. Tindakan operatif transisional mencakupi pengumuman penuntutan (indictment) dan keputusan (verdict); pernyataan soal amnesti, reparasi, dan pengampunan; dan pemberitahuan secara resmi soal konstitusi dan laporan, karena praktik-praktik transisional berbagai gambaran yang dikenal sebagai cara untuk mendemonstrasikan secara publik pemahaman kolektif yang baru tentang kebenaran. Secara historis, proses-proses transisional, entah soal penghukuman, lustrasi, atau penyelidikan, memiliki watak dan konsep yang serupa. Itu semua merupakan tindakan transisional yang diambil untuk berbagi pengetahuan publik yang baru, untuk memanifestasikan perubahan.18 Di sini hukum tampil memerankan fungsinya pada wilayah pinggiran, sebagaimana ia melakukan pemisahan dari rezim terdahulu dan melakukan pengintegrasian dengan suksesornya. Hukum transisional memiliki suatu kualitas “liminal”, kualitas wilayah perbatasan antara dua hal berseberangan, sebagaimana halnya hukum di antara dua rezim (yang lama dan yang baru). Sebenarnya, analisis tentang praktik hukum yang cermat menganjurkan bahwa keefektivitasannya yang tidak lumrah terdapat dalam kemampuan untuk mempengaruhi Pierre Bourdieu, “The Force of Law: Towards a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal (1987): 805, 814-840. 17 Lihat Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980. 18 Jadi, “penuntutan” (prosecution) secara historis merupakan bentuk “penyelidikan” (investigation). Lihat edisi kedua, (Oxford English Dictionary) di bawah kata “prosecution” definisi 3. Hal yang sama berlaku juga untuk “lustration”, yang menurut OED juga sejarah historis dipahami bermakna “to view” (memandang) atau “to survey” (meninjau). Lihat OED, di bawah kata “lustration”. 10 fungsi pemisahan dan fungsi integrasi – yang semuanya berada di dalam proses yang kontinu.19 Pada saat yang bersamaan, kedaulatan hukum transisional merupakan prosedurprosedur yang tidak tampak adil atau menarik minat – kekurangan pengadilan dalam penghukuman biasa, reparasi yang didasarkan pada kendali politik dan ambang batas (dan sering kali hak milik) temporal yang arbitrer secara legal, dan konstitusi yang tidak perlu permanen. Apa yang mencirikan secara khusus respon hukum transisional adalah soal keterbatasnnya, sifatnya yang parsial, yang dihidupkan dalam konstitusi sementara dan penghindaran hal-hal yang tak diinginkan, yang tergambar pada sanksi dan upaya reparasinya yang terbatas, dan yang tercermin dalam naratif historis dan ofisial (resmi) yang terpatah-patah dan terbatas. Hukum transisional adalah di atas segala hal yang simbolis – suatu santifikasi (pemurnian) sekular dari ritual dan simbol proses politik.20 Kendatipun bentuk-bentuk ritual tindakan operatif dan komunikasi sering dipikirkan untuk menggambarkan kekhasan karakteristik masyarakat primitif dan untuk membuatnya memudar dalam era modern,21 penyelidikan yang diambil di sini menganjurkan sebaliknya, yaitu menawarkan pemahaman yang komprehensif soal fenomenologi proses politik dan mengundang perbandingan dan evaluasi terhadap hakikat dan peran ritus dan simbol yang dikandungnya.22 Pola hukum pembuktian yang dipahami dalam bab-bab sebelumnya merangsang dan membentuk saluran politik, kendatipun merupakan muara pertemuan dari tradisi historis, hukum, dan politik, di mana pola-pola tersebut bergantung.23 Namun, apa yang membuat praktik-praktik transisional ini terpisah dari ritus dan ritual lainnya? Di atas apakah esensi paradigmatiknya berdasar? Proses-proses hukum transisional merupakan pengarah seperti tindakan-tindakan dalam masa transisi karena kemampuannya mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan material secara publik dan otoritatif yang menetapkan pergantian normatif antara rezim (yang lama dan yang baru). Bahasa hukum menyisipkan suatu tatanan baru dengan Tentang ritual perayaan, lihat Arnold van Gennep, The Rites of Passage, Chicago: University Press, 1960, yang aslinya dipublikasikan sebagai Les rites de passage, Paris: E. Nourry, 1909 (untuk konsep tentang proses ini dalam pengembangan individual); Victor W. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Strucuter, London: Routledge, 1969 (yang mendiskusikan konsep “liminalitas” dan relevansinya dengan transformasi individual); Nichola Dirks, “Ritual and Resistence: Subversion as a Social Fact”, dalam Nicholas Dirks, Geoff Eleyn, dan Sherry B. Ortner (ed.), Culture/Power/History: A Reader in Contemporary Theory, Princeton: Princeton University Press, 1944, 488. Tentang ritual secara umum, lihat Catherine M. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, New York: Oxford University Press, 1992. 20 Untuk pembahasan terkait lihat Murray J. Edelman, The Symbolic Uses of Politics, Urbana: University of Illinois Press, 1964; John Skorupski, Symbol and Theory: A Philosophical Study of Theories of Religion in Social Anthropology, Cambridge dan New York: Cambridge University Press, 1976; Dan Sperber, Rethinking Symbolism, Cambridge: Cambridge University Press, 1974. 21 Lihat Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, terj. Thomas Burger, Cambridge: MIT Press, 1974. 22 Lihat David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, New Haven: Yale University Press, 1988. Lihat juga Sean Wilentz (ed.), Rites of Power: Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985. 23 Tentang proses simbolik “evocation” [~ pemanggilan roh], lihat Sperber, Rethinking Symbolism, 143148. 19 11 legitimasi dan otoritas.24 Dalam bentuk simboliknya, jurisprudensi transisional merekonstruksikan perbedaan politis relevan melalui perubahan dalam hal status, keanggotaan, dan komunitas.25 Melalui proses-proses ini, apa yang sedang dikonstruksikan adalah perbedaan politik relevan di dalam rezim yang tidak liberal dan rezim yang liberal. Perbedaan kritis yang relevan akan menjadi sesuatu yang kontingen, termaknai, dan diakui sebagai hal yang legitim dalam pandangan warisan masa lalu masyarakat suksesor yang kemudian muncul. Dalam transformasi politik modern, adalah melalui praktik-praktik hukum bahwa masyarakat suksesor membuat perubahan politik liberalisasi, karena, dalam memediasi kemandekan dan pergantian normatif yang menggambarkan karakter khas transisi, pengembalian kepada hukum mencakupi dimensi fungsional, konseptual, operatif, dan simbolik yang penting. Sebagai suatu masalah permulaan, hukum mencontohkan atau menggambarkan respon rasional liberal terhadap penderitaan dan katastrofe atau kemalangan: bahwasanya ada, bagaimanapun juga, sesuatu yang harus dibuat. Dalam masyarakat liberal, alih-alih meninggalkan pengulangan sejarah, harapan akan perubahan diletakkan mengawang di udara. Bahkan dengan penautannya dengan perdebatan tentang keadilan transisional, masyarakat suksesor memberikan sinyal pembayangan yang rasional tentang kemungkinan akan suatu tatanan politis yang lebih liberal. Namun demikian, simbolisasi praktik-praktik hukum yang dibahas di sini mengedepankan sekaligus merangsang rasionalisme yang terdapat pada esensi kedaulatan hukum yang liberal.26 Dalam apa yang telah ditentukan secara khusus sebagaimana bentuk praktik-praktik ini yang dibatasi secara paradigmatik, maka pengembalian kepada simbolisme hukum menawarkan alternatif kunci terhadap responrespon yang keras dari retribusi dan pengganjaran dalam periode perubahan dan kekacauan politik. Respon hukum transisional bersifat hati-hati dan sengaja, berdasarkan pertimbangan tertentu, dibatasi pada hal-hal tertentu, dan membatasi dirinya pada halhal tertentu; dalam bentuk transisionalnya, proses-proses hukum yang diritualkan mendatangkan suatu perubahan yang gradual, perubahan yang terkontrol.27 Pengembalian semata kepada proses hukum supaya meredefinisi status, hak, dan tanggung jawab dan untuk membuka kran pembatas kekuasaan negara adalah, sampai pada tahap tertentu, suatu penerapan kedaulatan hukum yang dipadukan dengan sistem demokratik yang mapan. Itulah bentuk performatif dari tindakan-tindakan yang diambil dalam negara yang liberal. Sebagaimana halnya dengan pertanyaan tentang keadilan Lihat Edelman, Symbolic Uses of Politics. Untuk pembahasan menyangkut semacam ritus tentang “institusi”, lihat Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge: Harvard University Press, 1991. 26 Tentang “dimensi kognitif” lihat Lukes, “Political Ritual and Social Integration”, Sociology 9 (1975): 289. Lihat Skorupski, Symbolic and Theory; Kertzer, Ritual, Politics, and Power; Sperber, Rethinking Symbolism. 27 Lihat Judith Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials, Cambridge: Harvard University Press, 1986, dari perspektif teori politik.; Mary Duglas, Purity and Danger: Analysis of The Concepts of Pollution and Taboo, London and New York: Ark Paperbacks, 1984, 96 – dari perspektif antropologis. 24 25 12 transisional adalah “dikerjakan melalui”, masyarakat mulai menjalankan tanda-tanda dan ritus dari suatu tatanan liberal yang sedang berfungsi. Dalam hal ini, hukum transisional melampaui simbolik “semata” untuk menjadi pengarah ritus saluran politik modern. Tindakan-tindakan ritual mendatangkan adanya saluran di antara dua tatanan di sini, dari rezim predesesor (pendahulu) dan rezim suksesor.28 Dalam transisi kontemporer, yang dicirikan secara khusus oleh hakikatnya yang penuh kedamaian dan oleh kejadiannya yang selalu di dalam bingkai hukum, proses-proses hukum menjalankan “pengenyahan” yang kritis, inversi predikat yang menjustifikasi rezim yang tengah berkuasa, melalui proses publik yang memproduksi konstitutif pengetahuan kolektif dari pergantian normatif. Jadi, proses-proses hukum secara simultan mengingkari aspek ideologi rezim predesesor dan menjustifikasi perubahan ideologis yang menetapkan transformasi yang membebaskan. Sembari dalam pemahaman yang sedang mengemuka, hubungan antara hukum dan politik dipandang sebagai sesuatu yang terkandung dalam dukungan terhadap legalitas dan stabilitas konvensional, namun kedua hal tersebut (legalitas dan stabilitas) tidak dapat memediasi pergantian normatif. Oleh karenanya, penekanan pada satu sisi terhadap fungsi stabilisasi hukum dalam periode ketidakstabilan adalah suatu kesalahan,29 karena transisi memunculkan problem tentang bagaimana tatanan hukum – umumnya dipandang sebagai sistem yang tertutup dan sah-dari-dirinya-sendiri30 – memungkinkan perubahan normatif untuk dilakukan. Dari sini, teorisasi yang mengemuka sekarang ini sering kali mengkonseptualisasikan transisi sebagai hal yang diprediksikan pada perubahan mendasar dalam aturan sebagaimana teorisasi menyangkut konstitusionalisme transisional yang telah dibahas dalam bab 6. Namun, terkadang transisi terjadi tanpa perubahan meta-level semacam itu. Sebenarnya, tantangannya adalah bagaimana hukum memantapkan dan sekaligus, pada waktu yang sama, melampaui gagasan konvensional tentang hukum sebagai gagasan yang stabil, bahkan “keras kepala”, untuk mengkonstruk perubahan normatif. Perubahan di dalam dan melalui sistem hukum bergantung pada suatu reinterpretasi terhadap justifikasi relevan yang menjadi dasar dari tatanan normatif yang berlaku ataukah bergantung pada suatu pengembalian pada sumber independen dari norma-norma hukum alternatif. Alternatif pertama bersesuaian dengan suara familiar praktisi hukum tentang apakah bersandar pada fakta ataukah bersandar pada hukum, sementara yang disebut kemudian itu – introduksi tentang sumber normatif otonom – dipengaruhi melalui perubahan dalam pengakuan terhadap aturan yang berkenaan dengan sumber-sumber hukum yang valid.31 Pertanyaan tentang institusi mana yang Pierre Bourdieu, “Symbolic Power”, dalam Dennis Gleeson (ed.), Identity and Structure: Issues in the Sociology of Education, Driffeld, Eng. Nafferton Books, 1977, 112-119; lihat Lukes, “Political Ritual”, 302-305. 29 Lihat Kirchheimer, Political Justice, 430 (perjuangan tanpa keadilan politik hukum akan menjadi “kurang tertata”). 30 Lihat Gunther Teubner, Law as an Autopoietic System, Cambridge, Mass. Dan Oxford: Blackwell, 1993; Niklas Luhmann, “Law as a Social System”, 83 Northwestern Law Review83 (1989); Niklas Luhmann, Essay on Self-Reference, New York: Columbia University Press, 1990. 31 Lihat H.L.A. Hart, The Concept of Law, edisi kedua, Oxford-Clarendon Press 1994. 28 13 terbaik yang menyandarkan dirinya pada pemajuan perubahan normatif hukum telah menjadi subjek perdebatan substansial di dalam literatur transisi.32 Namun, sebagaimana dianjurkan oleh bahasan kita dalam keseluruhan isi buku ini, tak ada jawaban yang benar, karena hasil dari pilihan ini bersifat kontingen atau tergantung pada situasi-situasi politik soal kompetensi dan legitimasi yang menjembatani kedua rezim yaitu rezim predesesor dan rezim suksesor. Sering kali, badan legislatif yang sebelumnya berada di bawah aturan yang menekan menjadi bersifat kompromis, yang membuka jalan bagi pengadilan konstitusional yang diciptakan baru dan membuka jalan bagi para pelaku judisiari untuk menginkorporasikan norma-norma hak asasi manusia internasional.33 Pembalikan judisial kepada hukum hak asasi manusia internasional memungkinkan preservasi atau perlindungan dari masalah kontinuitas dan bahkan penggerakan lebih lanjut suatu prospektivitas konstruktif, dengan cara menerima tujuantujuan transformasi dan perubahan-perubahan normatif di dalam sistem hukum yang mapan. Kekuatan normatif yang signifikan dari hukum hak asasi manusia dalam masamasa transisi mendapatkan dari potensinya yang luar biasa kemampuan untuk memediasi bagian teoretis yang diperkirakan dari positivisme dan hukum kodrat, jadi yang melampau hubungan konvensional hukum terhadap politik. Akan tetapi, yang lebih umum adalah perubahan normatif tanpa perubahan dalam aturan-aturan yang telah diakui, suatu strategi yang bergantung pada suatu reinterpretasi terhadap dasar-dasar normatif yang merasionalisasikan definisi yang telah ada tentang status, hak, dan kewajiban. Proses-proses transformatif ini, hingga pada taraf tertentu, biasanya memiliki latar belakang, yang memainkan suatu peran yang tengah berlangsung di dalam sistem hukum kita. Dalam kedaulatan hukum yang mapan, perbedaan kategori hukum dan aturan berkaitan dengan standar yang beragam dari pengetahuan dan penalaran yang menjustifikasi definisi dan perubahan dalam status, kewajiban, dan hak-hak di bawah hukum. Namun, sebagaiman telah kita lihat, paradigma transisional keluar dari prinsip epistemologis yang dipadukan dengan kedaulatan hukum yang konvensional dengan menyusun tingkatan standar-standar pembuktian dan proses-proses penjustifikasian terhadap kategori-kategori hukum – sebuah de-diferensiasi di dalam hukum.34 Gambaran paradigmatik hukum transisional adalah bahwa hukum tersebut tampak jelas memajukan rekonstruksi pengetahuan publik, yang memahami afinitas operatif dan kontinuitas yang membuat pemisahan dari, dan pengintegrasian dari, pengubahan identitas politik. Lihat, msalnya, Ackerman, Future of Liberal Revolution. Untuk pambahasan di luar konteks transisional lihat Jeremy Waldron, “Dirty Little Secret”, Columbia Law Review 98 (1998): 510, 518-522; John Ely, Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review, Cambridge dan London: Harvard University Press, 1980. 33 Sumber yang terjadi kembali dari norma-norma luaran semacam itu adalah hukum hak asasi manusia internasional. Lihat, misalnya, Germany Constitutional Court Decision (24 Oktober, 1996), BverfGE, A2.2 BVR 1851/94; 2BvR 1853/94; 2 BvR 1875/94; 2BvR 1852/94, dicetak ulang dalam Juristenzeitung (1977): 142. 34 Untuk poin terkait berkenaan dengan pergantian, lihat Jacques Derrida, “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority”, Cardozo Law Review 11 (1990): 919. Tentang de-diferensiasi ritual, lihat René Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977, 300-301, 310-341. 32 14 Membangun suatu pengetahuan awal bersama yang berkenaan dengan warisan masa lalu merupakan suatu hal dari gaya bahasa atau gaya wicara dalam literatur dan diskursus tentang transisi.35 Akan tetapi, makna sebenarnya dari “kebenaran” dan hubungannya dengan transisi, analisis yang diambil di sini menganjurkan, tidak dibagibagikan secara universal tetapi, alih-alih, bersifat kontingen dan dinamis. Proses-proses hukum transisional paradigmatik bersandar pada perubahan yang benar-benar terpisah dalam pengetahuan publik yang relevan bagi tindakan transformatif operatifnya. Perbuahan dalam justifikasi publik yang dimiliki bersama yang mendasari pembuatan keputusan politik dan perilaku mengungkapkan sentralitas dari inovasi interpretatif di dalam konstruksi transisi.36 Apa yang relevan secara politik terhadap transformasi adalah ditentukan semata-mata oleh konteks transisional dan, khususnya, oleh warisan penggantian dan suksesi terhadap rezim kebenaran predesesor. Proses-proses hukum menawarkan cara-cara yang mapan tentang mengubah penalaran publik dalam tatanan politik, karena proses-proses itu sendiri didasarkan pada representasi otoritatif pengetahuan publik. Proses-proses hukum transisional dengan demikian berkontribusi pada perubahan-perubahan epistemologis dan interpretatif publik yang turut memberi kontribusi pada diterimanya transformasi. Pada saat yang bersamaan, proses-proses hukum transisional secara jelas dan energik mendemonstrasikan ketergantungan yang berkenaan dengan pengetahuan apa yang akan memajukan konstruksi pergantian normatif yang menyokong perubahan rezim. Namun demikian, dalam hal yang diperiksa dan dibahas di sini, kekuatan normatif potensial dari perubahan dalam pengetahuan publik bergantung pada tantangan-tantangan kritis terhadap penentuan kebijakan dan rasionalisasinya terhadap aturan predesesor. Oleh karena itu, “kebenaran-kebenaran” apakah yang ada di dalam masa transisi sering kali merupakan hal yang khusus dan tersendiri dan tetap merupakan hal yang signifikansi atau maknanya bersifat disproporsional. Sebagai contoh, identifikasi murni terhadap status korban sebagai seorang warga sipil dan bukannya sebagai seorang prajurit perang atau kombatan bisa meruntuhkan sebuah rezim (sekurang-kurangnya pada tataran normatif) dengan melemahkan makna ideologis kunci dari keamanan nasional negara yang bertanggung jawab terhadap penindasan masa lalu.37 Sebenarnya, reinterpretasi itu sendiri memindahkan makna pada pemerintahan sebelumnya dan menawarkan sebuah dasar yang baru bagi pemberlakuan kembali (reinstatement) kedaulatan hukum. Sebuah Teori tentang Keadilan Transisional Lihat, misalnya, Timothy Garton Ash, “The Truth about Dictatorship”, New York Review Books, 19 February 1998, hlm. 35; Priscilla Hayner, “Fifteen Truth Commissions 1974-1994; A Comparative Study”, Human Righst Quarterly 16 (1994): 600. 36 Untuk pembahasan yang mengenalkan dan mencakupkan poin terkait berkenaan dengan hubungan kebenaran dengan kekuasaan politik, lihat Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, terj. Collin Gordon et al., New York: Pantheon Books, 1980, 109-133; Charles Taylor, “Foucault on Freedom and Truth”, Political Theory12, No. 2 (1984): 152-183. 37 Lihat, misalnya, Nunca Más. 35 15 Sebuah paradigma tentang jurisprudensi transisional secara khusus menggambarkan proses perubahan politik. Paradigma transisional yang dikemukakan di sini berupaya mengklarifikasi relasi hukum dengan pengembangan politik dalam periode-periode perubahan yang radikal, sebagaimana proses-proses yang ditunjukkannya yang mengembalikan suatu masyarakat ke keadaan semula berdasarkan basis konsep liberalisasi politik. Persoalannya, apakah pengadilan, konstitusi, reparasi, pengujian administratif, penghukuman, atau penyelidikan historis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikedepankan dalam periode-periode transisi politik merupakan hal yang emblematik atau simbolik dari perubahan normatif; karena semuanya itu merupakan tindakan operatif yang mengarah pada pernyataan secara resmi dan publik tentang pengakuan dan pengukuhan suatu tatanan politik yang baru. Perspektif komparatif dan historis yang diadopsi di sini menganjurkan bahwa apa yang dipandang benar dan adil dalam masa-masa transisional bersifat kontingen secara politis tetapi tidak dalam pengertian arbitrer. Kendatipun ada klaim para realis bahwa fenomenologi transisional tidak sekadar merupakan produk dari situasi politiknya yang permanen, namun, sebaliknya, ia merupakan sebuah fungsi situasi politik kontemporer dan warisan sejarah ketidakadilan. Jadi, konsep keadilan transisional yang dikembangkan di sini mengandung makna suatu rekonseptualisasi tentang teorisasi yang berlangsung tentang hukum dan politik dan, juga, penekanan teori hukum kritis pada peran progresif untuk kedaulatan hukum yang sepenuhnya terjerat dalam politik.38 Untuk kontribusi khusus dan khas dari hukum transisional terhadap konstruksi proses perubahan politik adalah bahwa konstruksi tersebut dibatasi oleh dan sekaligus merupakan pelampauan politik. Sebagaimana hendak diprediksikan oleh sebuah teori kritis, hukum memainkan suatu prean konstruktif secara eksplisit, peran yang diritualisasikan oleh penyusunan perubahan interpretatif yang diterima atau dipahami sebagai transisi politik. Akan tetapi, pencaplokan politis terhadap bahasa dan proses keadilan menandakan simbol dan ritual perubahan yang legitim dan terukur. Kontribusi khusus hukum transisional terletak pada gabungan prosesnya yang diakui, proses yang terukur terhadap legitimasi dan perubahan politik yang gradual. Paradigma tentang jurisprudensi transisional yang sementara, yang dipolitisir secara berlebihan (hyperpoliticized) dihubungkan pada konsep tentang keadilan nonideal yang tidak sempurna (imperfect) dan tidak menyeluruh (partial). Apa yang jujur dan adil dalam situasi politik yang tidak biasa ditentukan tidak dari suatu konsep arkimedean yang ideal [mengikuti nama matematikawan kesohor dari Yunani, Archimedes] tetapi dari posisi transisional itu sendiri. Posisi menguntungkan ini memiliki hasil-hasil tertentu yang untuknya prinsip-prinsip keadilan membimbing masamasa perubahan politik. Apa yang dipandang jujur dan adil selama masa-masa inovasi politik radikal tidak perlu sampai pada pertimbangan atau pemikiran di bawah kondisi ideal dan prosedur reguler.39 Bahkan dalam masa-masa liberalisasi, proses-proses deliberatif (pertimbangan dan perenungan) sering kali dipotong, dan konsensus elektoral Lihat Roberto Mangabeira Unger, Social Theory: Its Situation and Its Task, A Critical Introduction to Politics, a Work in Constructivist Social Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 39 Lihat Rawls, Political Liberalism (teorisasi berkenaan dengan situasi-situasi non-transisional). 38 16 atau konstitusional yang mengatur pembuatan keputusan politik menjadi lemah dan berumur pendek. Ketika mengalami kekurangan dalam proses representatif yang utuh, legitimasi demokratik dari keputusan transisional membuatnya tergantung pada proses persetujuan selanjutnya. Oleh karena itu, konsep keadilan transisional yang ditekankan lebih lanjut di sini memiliki implikasi terhadap rekonseptualisasi teori pembangunan demokratik, seperti konstruksi hukum yang mencirikan secara khas masa-masa ini secara gradual menggantikan hamparan pandangan politik dan serbuan kesepakatan mempengaruhi pemahaman politik selanjutnya. Sebenarnya, dengan memodifikasi kondisi pembuatan keputusan dan konsensus, konstruksi hukum transisional melahirkan sedikit kesamaan terhadap teori demokrasi yang diidealkan.40 Imperatif diskontinuitas normatif sering kali mengalahkan perlindungan dari nilai-nilai lain dengan harapan bahwa apa pun yang keluar dari legalitas konvensional, persyaratan ini akan membayar secara penuh dalam konsolidasi demokratik. Setiap upaya selalu mengandung risiko, seperti argumen untuk pembatasan legalitas konvensional sering kali bersifat pratekstual alias mengelabui. Hanya dalam pusaran waktu sajalah akan tersingkap apakah, dan sampai pada tahap mana, kompromikompromi transisional yang dibahas dalam buku ini dijustifikasi dalam konsolidasi demokrasi liberal. Pembatasan otoritatif tentang apakah kejujuran dan keadilan dalam momenmomen transisi tidak terjadi dalam suatu ruang hampa melainkan dilesatkan menembus layar belakang panggung warisan sejarah ketidakadilan. Pencarian keadilan ditempatkan dalam kondisi politik transisi. Dalam konteks inilah, makna sesungguhnya dari kedaulatan hukum bersifat kontingen secara historis dan politis, dan muatannya dijejali dengan pemahaman-diri masyarakat tentang hakikat dan sumber pemaksaan dan penindasan di masa lampaunya. Warisan ini merupakan semacam papan loncat (springboard) bagi imajinasi masyarakat tentang keadilan transisional. Melintasi aneka kebudayaan, makna keadilan transisional disusupi dengan dimensi restoratif dan transformatif. Dari perspektif ini, bahkan pengeluaran prosedural dari nilai-nilai internal dalam legalitas konvensional dan teori-teori keadilan dapat diperjelas. Jadi, sebagai contoh, peradilan pidana transisional tidak dijustifikasikan dalam bahasa akuntabilitas individual dan retribusi tetapi, malahan, berisikan rasionalisasi politik yang eksplisit. Sama halnya juga, reparasi transisional memperdamaikan tujuan-tujuan korektif ideal dengan sasaransasaran distributif atau sasaran lainnya yang berkaitan dengan urgensitas dari momenmomen tersebut. Fenomena transisional mencerminkan suatu keseimbangan dan akomodasi teori-teori ideal hukum dan situasi-situasi politik transisi. Mengakui hal ini membawa konsekuensi definisional yang signifikan yang mengizinkan suatu pemikiran positif yang lebih komprehensif dari periode-periode ini, termasuk juga evaluasi normatif yang lebih menarik minat dan kritik tentang fenomenologi hukum transisional. Rekonsepsi yang dikedepankan di sini mencirikan secara khas hukum transisional berkenaan dengan keadilan yang tidak sempurna (imperfect) dan tidak utuh-menyeluruh (partial) tetapi hukum yang tepatnya untuk alasan ini menyediakan ruang kritis 40 Lihat ibid. 17 berkaitan dengan situasi politik yang tidak biasa yang menentukan konteks keadilan dalam masa-masa tersebut. Ketersediaan kosa kata tentang jurisprudensi transisional dan konsepsi tentang keadilan transisional bisa juga menerangi konsepsi tentang keadilan yang dipadukan dengan situasi-situasi non-transisional. Keadilan Transisional dan Identitas Liberal Fenomena pencarian keadilan yang dibahas di sini terikat secara erat pada pembentukan identitas politik liberal. Sebagaimana dianjurkan dalam bahasan kita pada bagian awal di depan, pembalikan kepada legalisme, kendatipun kontingen, adalah simbol khas dari negara liberal, dengan keadilan transisional yang merekonstruksi identitas politik di atas basis juridis dengan menggunakan diskursus hak dan tanggung jawab. Lebih lanjut, sembari muncul menjadi dukungan yang semakin memudar terhadap suatu kedaulatan hukum yang ideal dalam transisi, bagaimanapun juga dalam negara liberal itulah terdapat pemahaman yang semakin meningkat secara intens terhadap kepentingan publik, yang merupakan bukti terhadap spektrum respon transisional paradigmatik, termasuk pembuatan konstitusi, amnesti, rekonsiliasi, dan pemaafan.41 Tujuan respon-respon ini terhadap visi tentang keadilan yang fragmentaris tetapi terbagi-bagi yaitu bahwa, di atas segalanya, perlu ada perbaikan atau upaya korektif. Apa yang merupakan capaian paling tinggi adalah tuntutan yang visibel akan upaya perbaikan melalui hukum (remedy), pengembalian, pemulihan menyeluruh, penyatuan politik – suatu dorongan yang menyatupadukan nilai-nilai eksternal terhadap nilai-nilai dari teori ideal tentang keadilan. Sebagai contoh, konstitusionalisme transisional memahami tidak hanya dengan berorientasi ke depan semata melainkan juga dengan menengok ke belakang dalam hal dimensi-dimensi remedial; ia beroperasi dalam pola korektif, yang mengkonstruksikan suatu “pembalikan” normatif (jika tidak disebut historis) kepada identitas politik liberal suatu negara. Sama halnya juga, peradilan pidana transisional berjalan jauh melampaui soal penghukuman terhadap pelaku individual untuk memenuhi tujuan-tujuan korektif prospektif suatu masyarakat. Sampai pada taraf bahwa keadilan transisional berimplikasi pada pembalikan pada makna korektif, keadilan transisional itu menawarkan identitas suksesor alternatif yang berpusat pada kesatuan politik. Keadilan transisional menawarkan sebuah cara untuk merekonstitusikan atau menetapkan ulang semangat kolektif – yang mengatasi keterpilahan berdasarkan ras, etnis, dan agama – yang didasarkan pada identitas politik yang muncul dari warisan khas masyarakat akan kegentaran dan ketidakadilan. Sembari hal ini perlu didasarkan pada pembangkitan pemahaman diri kritis, namun keadilan transisional berdiri tegak di atas diskursus juridis tentang hak dan tanggung jawab yang menawarkan baik pandangan normatif transenden maupun suatu konsep aksi pragmatis. Fenomena hukum transisional yang dibahas dalam keseluruhan buku ini menganjurkan bahwa makna kebebasan, keamanan, dan kedaulatan hukum berbedabeda antar-negara dan kultur, karena, dalam pencerminan respon-responnya terhadap 41 Lihat, misalnya, Ackerman, Future of Liberal Revolution 18 manifestasi khusus aturan yang represif, makna-makna tersebut juga mengindikasikan bahwa kedaulatan hukum mengandung arti sesuatu yang lebih dari sekadar aturan nonarbitrer dan mendukung sesuatu yang reguler, umumnya prosedur-prosedur yang bisa diterapkan. Apa yang membedakan secara khas jurisprudensi transisional kontemporer adalah bahwa konstruksi kedaulatan hukumnya merespon penganiayaan sistematik di bawah imprimatur legal atau pemegang kewenangan hukum. Yang mendasari fenomena hukum transisional kontemporer adalah suatu konsepsi tentang ketidakadilan negara sebagai kebijakan penindasan yang sistematik. Ketika negara menindas dan menyiksa secara sistematis para warganya berdasarkan perbedaan ras, etnis, agama, keyakinan politik, maka penganiayaan tersebut tidak semata suatu pengingkaran yang arbitrer terhadap kedaulatan hukum. Oleh karena itu, hukum transisional kontemporer merespon jenis aturan khas ini, yaitu aturan yang menindas. Respon transisional terhadap penganiayaan sistemik di bawah bendera hukum memperlihatkan secara nyata suatu penghancuran performatif terhadap perbuatan-perbuatan salah sebelumnya yang dilakukan di dalam sistem hukum. Respon-respon transisional, seperti pengadilan konstitusional yang baru,42 konstitusi, dan berbagai pertimbangan dan langkah lainnya, membuktikan adanya penganiayaan politis yang menyemati paruh kedua abad kedua puluh.43 Proses-proses hukum transisional dalam hal penyelidikan dirancang secara baik untuk menegakkan pola-pola dan sistematika dalam kebijakan penganiayaan yang dilakukan negara; sesungguhnya, cakupan utuh dari kebijakan yang menindas dan menyengsarakan itu hanyalah manifes dalam respon-respon hukum. Apakah penganiayaan semacam itu dilakukan di atas dasar pertimbangan rasial, etnisitas, nasionalitas, agama, atau ideologi, hukum transisional mencerap dari dan memberi respon terhadap implikasi politik represi yang merupakan kebijakan negara.44 Respon-respon transisional yang berulang-ulang yang mengarahkan perhatiannya pada penganiayaan sistemik berupaya menampik hierarki askriptif yang terkait dengan rezim lama. Distingsi soal “teman/musuh” yang disepakati rezim legal, sebagaimana dibahas dan dianjurkan dalam keseluruhan isi buku ini, merupakan wabah endemik yang tak bisa hilang dari rezim otoritarian. Responrespon ini mendasari penampikan terhadap logika penganiayaan dari rezim lama dan, dengan demikian, penolakan terhadap kekuasaannya.45 Jurisprudensi transisional menyingkapkan basis bagi nilai-nilai demokrasi yang operatif di dalam masyarakat pada waktu perubahan politik.46 Siklus keadilan 42 Lihat bab 6. Lihat juga Ruti Teitel, “Post-Communist Constitutionalism: A Transitional Perpective”, Columbia Human Rights Law Review 26 (1994): 167. 43 Lihat Ruti Teitel, “Human Rights Genealogy”, Fordham Law Review 66 (1967): 301 44 Tentang pandangan klasik, lihat Leo Strauss, On Tyranny, ed. Victor Gourevitch dan Michael S. Roth, edisi revisi, New York: Free Press, 1991. 45 Lihat Schmitt, The Concept of the Political, 26-29 46 Pandangan ini membagi-bagi beberapa afinitas tertentu dengan teorisasi politik Jürgen Habermas, Sheldon Wolin, Edmond Cahn, Judith Shklar, dan yang lainnya yang memberikan penekanan pada liberalisme yang ditempatkan dalam warisan ketakutan dan ketidakadilan. Lihat Jürgen Habermas, “On the Public Use of History”, dalam The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians’ Debate, ed. dan terj. Shierry Weber Nicholsen, Cambridge: MIT Press, 1989, 229-240; Judith Shklar, “The Liberalism of Fear”, dalam Nancy L. Rosenblum (ed.), Liberalism and The Moral Life, Cambridge: 19 transisional mengilustrasikan suatu kaitan antara fenomena hukum ini dan konstruksi liberalisasi. Secara historis, dalam transisi dari bentuk monarkis ke rezim republikan, ritual yang paling kentara dari proses perubahan politik adalah pengadilan raja-raja – suatu ritual yang menyimbolkan penundukkan raja terhadap keinginan rakyat dan menandakan agungnya kedaulatan rakyat.47 Keadilan suksesor abad kedua-puluh merekonstrusikan lebih lanjut relasi individual dengan negara: jadi, prinsip-prinsip generatif pengadilan Nuremberg pasca-perang tentang tanggung jawab individual menekankan peran individual sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat. Hal yang sama adalah benar juga menyangkut perubahan konstitusional dari masa di mana hak-hak individual terlindungi.48 Dalam fenomena transisional kontemporer, visi demokratik pasca-perang sekarang ini sedang dalam proses digantikan dengan pemahaman yang lebih kompleks dan mengalir tentang kedaulatan dan tanggung jawab yang menengahi antara makhluk individual maupun kolektif, tatanan nasional dan internasional. Relasi dinamis yang meningkat antara individu dan negara dalam kawasan publik global yang berubah cepat mempengaruhi pemahaman personal dan tanggung jawab kolektif, yang dengan demikian membawa perubahan terkait dalam konsepsi tentang demokrasi. Di sanalah terkandung ekspansi tanggung jawab individual dan tanggung jawab negara sebagai sebuah masalah teoretis dan, dengan demikian, berganti dalam posisi kewenangan dan agensi, dengan hukum transisional yang memediasi pilahan individual/kolektif untuk mencapai tindakan privat secara murah meriah yang bertentangan dengan dasar-dasar pertimbangan diambilnya kebijakan negara.49 Jurisdiksi hukum yang diperluas dan perubahan dalam kedaulatan membantu mengkonstruk pergantian otoritatif yang menetapkan transisi politik. Tetapi perubahan semacam itu sering kali juga menempatkan kedaulatan, jurisdiksi, dan tanggung jawab itu sendiri dalam perubahan yang tiada henti, yang bergantung pada karakter perilaku negara, sebagai contoh, kepatuhannya terhadap atau pengingkarannya dari kewajiban di bawah hukum internasional. Tanpa mempedulikan liabilitas atau tanggung jawab hukum yang diperluas sebagai masalah teoretis, penerapan prinsip-prinsip ini bersifat jarang dan umumnya dibatasi pada kasus-kasus yang melibatkan prinsip-prinsip pembatasan tambahan, seperti sebuah pola yang ditunjukkan dari penganiayaan.50 Namun demikian, dengan mereinterpretasikan kewajiban negara terhadap warganya melalui pergantian kritis terhadap kedaulatan dan jurisdiksi, praktik-praktik transisional kontemporer secara Harvard University Press, 1989, 21; Edmond N. Cahn, The Sense of Injustice: An Anthropocentric View of Law, New York: New York University Press, 1949. 47 Lihat Michael Walzer, Regicide and Revolution, terj. Marian Rothstein, New York: Columbia University Press, 1974 (yang membahas soal pengadilan terhadap Louis XVI). 48 Lihat Louis Henkin, The Age of Rights, New York: Columbia University Press,1990. 49 Lihat Prosecutor v Tadić, Kasus No. IT-94-I-AR72, Keputusan berdasarkan Mosi Pembela (Pihak Terdakwa) untuk Banding Interlokutoris (yang dikeluarkan dan berkekuatan hukum sementara) tentang Jurisdiksi (Sidang Banding, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 50 Untuk pembahasan tentang pengaruh globalisasi terhadap penyebaban dan agensi, lihat Samuel Sheffler, “Individual Responsibility in a Global Age”, dalam Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller, dan Jeffrey Paul (ed.), Contemporary Political and Social Philosphy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 20 potensial meningkatkan energi jaminan hak asasi manusia yang ditampilkan pertama kali secara samar-samar dalam era pasca-perang.51 Rekonseptualisasi gagasan-gagasan utama yang berkenaan dengan relasi di antara individu dan negara memegang hasil-hasil penting bagi pemahaman akan diri juga. Dalam pemajuan jurisprudensi transisional tentang pergantian normatif, peran hukum sering kali secara umum bersifat simbolik. Namun, pada tataran operatif, keadilan transisional mempengaruhi individu: Apakah melalui proses-proses pengadilan, reparasi, konstitusi, administratif, atau melalui langkah-langkah lainnya, legalitas transisional merekonstruksikan aturan dan syarat-syarat keanggotaan politis, representasi, dan partisipasi yang adalah hal yang mendasar bagi tempat individu dalam komunitas. Liberalisasi perubahan normatif bergantung pada redefinisi pemahaman status individual, hak, dan kewajiban, juga pembatasan parameter kekuasaan negara. Efek permulaan dari tindakan pencarian-keadilan rezim suksesor terdapat pada level tindakan individual, yang pada gilirannya menggantikan identitas politik negara dan sekurang-kurangnya secara potensial merancang suatu pemahaman liberal yang baru. Pengaruh fenomena keadilan transisional terhadap pembangunan identitas politik negara dalam masa-masa disturbansi (yang penuh gejolak perubahan) membangkitkan sebuah pertanyaan terkait yang berkenaan dengan masa transisional versus masa nontransisional. Kenyataannya, pertanyaan soal hubungan keadilan transisional dengan masa-masa biasa memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah pertanyaan yang dengannya buku ini mulai ditulis: Sampai pada tahap manakah teori-teori ideal tentang keadilan relevan dengan masa-masa transisi? Buku ini menjawab bahwa teori ideal semata-mata bukanlah tongkat pengukur yang relevan yang dengannya kita bisa menimbang-nimbang tindakan hukum dalam masa-masa transisi tersebut. Perspektif komparatif dan historis yang dikedepankan di sini menuntut suatu pemahaman akan keadilan non-ideal, keadilan yang “dikompromikan” yang secara bersamaan diwarnai oleh dan sekaligus mengukuhkan kondisi-kondisi yang di bawahnyalah keadilan seperti itu dipilih. Pengakuan terhadap konsep keadilan ini memiliki hasil-hasil tertentu bagi dimensi kedua pertanyaan kita: Sampai pada tahap manakah semestinya keadilan transisional itu dimanfaatkan pada masa-masa biasa? Fenomena yang diperiksa di sini terjadi secara umum di bawah rezim suksesor pertama pasca-penindasan, yang responresponnya dinyatakan secara temporal juga dengan modalitas perubahan transformatif yang telah dibahas di atas. Menjadi perlulah untuk membuka pagar periode transisi yang dikonstruksikan dengan tindakan paradigmatik jurisprudensi yang berlaku sebagai ritual proses perubahan politik. Namun, tanpa mempedulikan lorong waktu, kejadian-kejadian yang menyela, perubahan politik, problem keadilan transisional, ketika semuanya itu ditinggalkan tanpa terpecahkan, tidak begitu saja menghilang.52 Pencarian keadilan transisional tetap berlangsung, tidak bisa mengikuti pemahaman konvensional yang Lihat, misalnya, Velásquez-Rodriíguez Compensation Judgement, Inter-Am. Ct. H.R., Ser. C, No. 4 (1989). 52 Tentang pentingnya soal waktu, lihat Jeremy Waldron, “Superseding Historic Injusticeaa”, Ethics 103 (1992): 4. 51 21 berkenaan dengan respon-respon terhadap kesalahan-kesalahan, yang umumnya dipikirkan mengabur bersamaan dengan berlalunya waktu. Bertahannya problemproblem hak dan asumsi-asumsi suksesor tentang kewajiban terhadap pengingkaran masa lalu dari kedaulatan hukum sering kali – tak peduli adanya selang waktu – mengaburkan pemahaman yang di dalamnya tindakan-tindakan ini merupakan subjeksubjek yang sangat dihargai bagi keadilan transisional. Namun, ketahanan klaim-klaim tersebut selama jangka waktu yang lama, yaitu klaim tentang kesalahan masa lalu, sekali lagi mengungkapkan independensi pertanyaan-pertanyaan ini dari penantian biasa terhadap perubahan-perubahan dalam kekuasaan politik. Keadilan transisional menganjurkan bahwa asumsi tanggung jawab negara yang tengah dibebankan sekarang ini bagi klaim yang dikaitkan dengan masa lalu dijalankan secara bersama-sama dengan identitas politik yang stabil, yaitu, merealisasikan lebih dari sekadar keadilan parsial sering kali menantikan proses berlalunya waktu.53 Kendatipun ketahanan dari klaim yang berkaitan dengan masa lalu juga memunculkan konflik yang potensial, kemungkinan memposisikan klaim-klaim tradisionalis berseberangan dengan yang lain merupakan nilai-nilai liberal yang lebih berorientasi ke depan. Akan tetapi, penyelimutan atau perlindungan terhadap identitas, memegang suatu tuntutan normatif dan juga tuntutan fungsional yang tak bisa disepelekan; bagaimanapun juga, indentitas politik-lah yang menekankan kemungkinan kesatuan dan keadilan korektif – suatu visi penebusan. Sama halnya juga, keadilan transisional menawarkan suatu cara yang terkontrol untuk melakukan pembaruan, cara yang lebih bisa terukur daripada perubahan-perubahan yang dituntun sendirian berdasarkan sumber-sumber normatif lain, seperti tuntunan moral.54 Sebenarnya, resolusi transisional muncul mengatasi atau mencakupi, sekurang-kurangnya untuk sementara, nilai-nilai transenden yang warnai aspek norma hak asasi manusia yang mampu memediasi batas-batas politik transisional.55 Kendati jurisprudensi transisional menduduki paradigma yang bisa dikenal, jurisprudensi itulah yang ada dengan afinitasnya terhadap hukum dalam situasi-situasi non-transisional. Sebenarnya, seseorang bisa saja memikirkan jurisprudensi transisional sebagai pencontohan yang lebih baik yang menghidupkan konflik dan sebaliknya mengkompromikan sesuatu yang laten di dalam hukum dan, khususnya, menerangi hubungan hukum dengan politik. Satu tempat yang dilihat di sini terdapat dalam hubungan antara jurisprudensi transisional dan hukum hak asasi manusia, karena terbukti bahwa pemberlakuan paling tegas hukum hak asasi manusia terjadi dalam periode-periode transisional. Kendati norma-norma hak asasi manusia secara umum Lihat secara umum Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: Belknap Press, 1986, 168-169. Lihat juga Jürgen Habermas, “Kant’s Idea of Perpetual Peace with the Benefit of Two Hundred Years’ Hindsight”, dalam James Bohman dan Matthias Lutz-Bachmann (eds.), Perpetual Peace, Essay on Kant’s Cosmopolitan Ideal, Cambridge dan London: MIT Press, 1997. 55 Lihat Theodor Meron, “War Crimes Law Comes of Age”, American Journal of International Law 92 (1998); 462; Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1989, 10-25 yang membahas soal konvergensi dalam definisi normatif. Lihat secara umum 1998 Yearbook of International Humanitarian Law, The Hague: T.M.C. Asser Press, 1998-1958. 53 54 22 dikodifikasi, penerapannya pada umumnya terjadi dalam masa-masa transisional, ketika ada kesiapan yang lebih besar terhadap percobaan dengan skema normatif alternatif. Sebuah contoh adalah tribunal ad hoc terhadap kejahatan perang yang didirikan untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia selama konflik Bosnia dan Rwanda terjadi. Sementara pelaksanaan keadilan secara utuh adalah tidak mungkin, namun bagaimanapun juga bentuk simbolik paradigmatik ini menjalankan atau memerankan fungsi biasa dari pengungkapan pergantian dalam posisi otoritas dalam masa transisi. Lebih jauh, pada tingkat minimumnya, respon-respon dalam periode ini yang menekankan pemeliharaan rekaman menyokong kemungkinan keadilan yang lebih menyeluruh di masa depan. Namun demikian, akomodasi dan penentuan tempo ini seharusnya tidak dibingungkan dengan keadilan ideal. Respon-respon transisional mestinya tidak digeneralisasikan sebagai standar-standar hak asasi manusia tentang bagaimana merespon kekerasan, baik yang sedang berlangsung sekarang (dalam masa transisi) ataukah terjadi di masa lalu. Bagaimanapun, normalisasi terhadap responrespon transisional akan kehilangan satu hal, yaitu pesan transformatif inti: keyakinan dalam kemungkinan manusia untuk mencegah pengulangan tragedi masa lalu dalam negara yang sedang menjalankan proses liberalisasinya. Sebenarnya, kekuatan-kekuatan normatif hukum hak asasi manusia adalah semacam kekuatan yang memampukan transformasi berjalan terus bahkan dalam situasi-situasi non-transisional sekalipun. Mendorong dan terus mempertahankan identitas transisional yang dipegang kukuh menghadapi dua risiko lanjutan. Yang pertama berkaitan dengan cakupan sampai di mana transisi itu muncul sebagai yang merasionalisasi atau memahami masa lalu terlalu banyak dan terlalu jauh. Hermeneutik transisional yang paling mendasar adalah pengetahuan-diri yang historisis yang tersedia hanya secara ex post [setelah kejadian berlangsung, jadi pengetahuan yang didapatkan setelah suatu kejadian terjadi dan dicermati], dan bahayanya adalah bahwa hermeneutik ini bisa diperlemah jika kesalahan masa lalu sepertinya dibenarkan atau dijustifikasi oleh kemajuan yang terjadi kemudian yaitu kemajuan yang mengarah pada liberalisasi. Kedua, pencarian negara transisional untuk kesatuan bisa begitu mudah sekali menjadi premis bagi rumusan yang secara inheren tidak stabil yang diperlakukan entah sebagai mitos atau entah sebagai visi normatif yang tak terrengkuh. Dalam kedua hal tersebut, risikonya adalah bahwa asumsi negara tentang identitas politik yang didasarkan pada kesatuan mungkin melemahkan kemungkinan perubahan politik. Perlindungan statis semacam itu terhadap identitas sangatlah tidak liberal. Sebaliknya, sosok liberal menekankan perlunya pemenuhan “gizi” bagi – dan dengan demikian mempertahankan – modalitas transisional sebagai suatu ruang kritis di antara hal yang bersifat praktis-praksis dan redemptif atau bermakna penebusan dalam imajinasi politik. 23 Epilog: Keadilan Transisional dan Normalisasinya – Fin de Siècle Pikirkanlah sampai pada tahap apa diskursus yang berulang-ulang selama tahun-tahun terakhir dari abad kedua-puluh adalah satu dari keadilan transisional. Ada tugas yang persisten atau lestari menyangkut apologi atau pemaafan, reparasi atau pemulihan, memoir atau kisah sejarah (individu dan kolektif), dan semua cara pertanggungjawaban berkenaan dengan penderitaan dan kejahatan masa lampau. Contoh-contoh banyak berkisar seputar penanganan terhadap kontroversi-kontroversi berkenaan dengan Perang Dunia II, kehilangan rekening bank, restitusi atas harta milik, reparasi terhadap buruhbudak, pengembalian objek-objek yang sebelumnya telah dirampas. Barangkali contoh yang paling jelas untuk normalisasi jurisprudensi transisional adalah dimasukkannya pengadilan atau tribunal militer internasional pasca-perang ke dalam usulan pengadilan pidana internasional (ICC – Intenational Criminal Court), sebuah institusi internasional baru di penghujung abad kedua-puluh. Di sini tampak jelas sekali diskursus yang berkembang dan meluas, yang sebelumnya tak pernah ada, menyangkut klaim-klaim hak dan pertanggungjawaban. Keberpulangan kepada ritual-ritual yang dipadukan dengan perubahan politik yang dibahas dalam buku ini terjadi pada waktu periodisasi dimensi sentenial (ratusan tahun) dan milenial (ribuan tahun). Keberpulangan kepada ritual-ritual ini dalam konteks meta-transisi memunculkan suatu upaya pervasif atau meluas untuk mengkonstruk kiatkiat atau cara-cara kolektif. Dalam momen kontemporer sekarang ini, ritual sosial dari kiat atau cara tersebut muncul tidak untuk diasalkan pada atau diambil dari agama tetapi dari hukum. Ini merupakan ritus sekular dan simbol perayaan, meramalkan bukannya apokalipse atau wahyu juga bukan soal mesianisme atau penyelamatan, melainkan tentang apa yang muncul menjadi konsepsi transisional paradigmatik: tentang perubahan yang terbatas. Urgensitas jurisprudensi transisional adalah bahwa ia menawarkan penutupan terhadap apa yang dibawa oleh perayaan tersebut. Tetapi selalu demikianlah harga yang harus dibayarnya. Setiap tindakan transisi berimplikasi pada resolusi yang ambivalen. Ritus-ritus liberal ini melaksanakan perayaan politik dengan mengkonstruksikan diskontinuitas dan kontinuitas, destruksi dan reproduksi, disapropriasi dan reapropriasi (pelepasan harta orang lain dan perampasan kembali harta orang lain), disavowal dan avowal (penolakan dan persetujuan). Ritual-ritual ini mencoba menyingkirkan ke masa lalu semua hal terburuk dari abad ini, sembari juga mengusulkan suatu narasi bersama yang bisa diterapkan untuk masa depan. Dengan praktik-praktik ini, sebuah garis ditarik untuk membuat demarkasi atau batas parameter dari memori kolektif masa lalu itu untuk dipelihara: apa yang harus diingat dan apa yang ditekan atau dipendam; apa yang perlu ditinggalkan dan apa yang perlu divalidasi atau diperkuat kembali; apa yang perlu dan tidak bisa tidak diberi perhatian besar dan apa yang akan tetap dipertentangkan. Pembaruan dimungkinkan dengan membiarkan pergi segala kisah ketidakadilan historis abad yang telah lalu itu dan bergerak dari suatu 1 pluralitas identitas politik yang bertentangan ke suatu narasi yang berlaku umum. Pada dasarnya, praktik-praktik transisional memiliki karakter ambivalen, tempat praktikpraktik ini dalam perubahan politik terdapat dalam upaya penyatuan; tetapi, masih saja ada yang lolos. Keadilan transisional bersifat parsial dan terbatas. Sumber terhadap penyelesaian semacam itu mengandaikan adanya kompromi; potensialitasnya tergelar dalam kemampuannya untuk menetapkan kembali atau menegakkan kembali suatu komunitas. Sumber bagi keadilan transisional memiliki karakter politiknya yang khas – yaitu konsensus yang dipaksakan dan suatu penghindaran pertimbangan soal individualisme yang mengkarakterisasikan konstitusionalisme modern – sembari bentuk-bentuk transisional berkompromi dengan simbol-simbol kecil dari kebiasaan suatu aturan hukum negara. Praktik-praktik ini mengungkapkan suatu rangkaian konsep dan gagasan yang unik dan tak biasa terhadap momen kontemporer sekarang ini. Inilah keberpulangan kepada jurisprudensi transisional, bukan soal proyek mendasar yang besar untuk melakukan reformasi melainkan soal penilaian terhadap situasi yang serius, bukan sekadar soal pemodernisasian keyakinan dalam hal kemajuan moral dari masa-masa awal abad kedua-puluh melainkan juga bukan suatu konservatisme yang sia-sia atau dekadensi yang fin de siècle. Kompromi politik pastinya merupakan suatu tanda perenial atau tanda abadi tentang demokrasi yang senantiasa hidup; tetapi pikirkanlah signifikansi normalisasi dari paradigma ini dalam dan melalui hukum. Konsep contoh yang paling penting dari perubahan terbatas ini utamanya mengedepankan kesadaran diri tentang kekuatan konstruktif hukum dan tentang faktor-faktor pembatasnya. Di penghujung abad berdarah ini, apa yang tampak paradigmatik adalah respons terhadap bencana politik: keadilan sebagai yang bersifat politis, hukum tanpa ilusi, namun yang senantiasa menyuburkan tumbuhan harapan yang kecil tetapi semakin membesar. 2 Catatan Pengantar 1. Lihat Ruti Teitel, “How Are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” (makalah yang disiapkan untuk Council on Foreign Relations New York, N.Y., 17 Mei, 1990). Pendahuluan 1. Karya-karya selain studi kasus atau pendekatan regional sering kali terbatas pada momen historis tertentu. Lihat misalnya John Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982 (berfokus pada masa pascaperang). Untuk pembahasan klasik tentang masalah keadilan politis, lihat Otto Kircheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Westport, Conn: Greenwood Press, 1980. 2. Lihat Bruce A. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, New Haven: Yale University Press, 1992; Carlos Santiago Nino, Radical Evil on Trial, New Haven: Yale University Press, 1996; John Herz, “An Historical Perspective”, dalam Alice H. Henkin (ed.), State Crimes: Punishmentor Pardon, Queenstown, Md: Aspen Institute, 1998. Untuk pendekatan komparatif, lihat esai-esai dalam Guillermo O Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perpectives, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Lihat juga Juan J. Linz dan Alfred Stepan, Problems of Communist Euripe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996 (mengeksplorasi proses-proses transisi dan konsolidasi dari perspektif komparatif. Lihat misalnya Jaime Malamud-Goti, “Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?” Human Rights Quarterly 12, No. 1 (1990): 1-16. 3. Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1979, 15-66; R. B. J. Walker, Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 123-24. Untuk ringkasan tentang pandangan realis dalam teori internasional, lihat John H. Herz, Political Realism and Political Idealism, Chicago: Chicago University Press, 1951; Martin Wight, International Theory: The Three Traditions, London: Leicester University Press untuk Royal Institute of International Affairs, 1990; J. Ann Tickner, “Hans Morgenthau’s Principles: A Feminist Reformulation”, dalam James Der Derian (ed.), International Theory: Critical Investigations, New York: New York University Press, 1995, 53, 55-57. 4. Lihat umumnya Linz dan Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation; O’Donnel et al., (eds.), Transitions from Authoritarian Rule (kumpulan esai yang umumnya berpendekatan regional). Lihat juga Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratizaton in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, 215; Stephan Holmes, “The End of Decommunization”, East European Constitutional Review 3 (musim gugur 1994), 33. 5. Untuk argument serupa, lihat Huntington, Third Wave, 231. 6. Lihat Ackerman, Future of Liberal Revolution, 69-73; E. B. F. Midgley, The Natural Law Tradition and the Theory of International Relations, New York: Barnes & Noble Books, 1975, 219-31, 350-51. 7. Anne-Marie Slaughter, “International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda”, American Journal of International Law 87 (1993), 205. Tradisi Liberal dalam Jurisprudensi melatarbelakangi pendekatan tersebut. 8. Ekspresi paradigmatik tentang pandangan teori liberal tentang hukum dan politik dapat ditemukan dalam John Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, dan John Rawls, “The Domain of the Political and Overlapping Consensus”, New York University Law Review 64 (1989), 1 233. Tentang kaitan antara teori tentang hak dan demokrasi, lihat Jeremy Waldron (ed.), Theories of Rights, Oxford: Oxford University Press, 1984. Lihat juga Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press, 1986; Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press, 1977. 9. Kumpulan penting esai-esai studi hukum kritis mencakup James Boyle, Critical Legal Studies, New York: New York University Press, 1992, dan David Kairys, The Politics of Law: A Progressive Critique, New York: Pantheon Books, 1990. Lihat juga Mark Kelman, A Guide to Critical Legal Studies, Cambridge: Harvard University Press, 1986; James Boyle, “The Politics of Reason: Critical Legal Theory and Local Social Thought”, University of Pensylvania Law Review 133 (1985), 685 (membicarakan realisme legal, teori linguistik dan teori Marxis). Untuk tinjauan kritis tentang isu legal internasional, lihat Nigel Purvis, “Critical Legal Studies in Public International Law, World Order, and Critical Legal Studies”, Stanford Law Review 42 (1990): 81. Untuk analisis kritis tentang jurisprudensi Amerika, lihat Mark Tushnet, Red, White, and Blue, Cambridge: Harvard University Press, 1988. 10. Lihat Ackerman, Future of Liberal Revolution, 11-14; Hannah Arendt, On Revolution, New York: Viking Press, 1965, 139-78. 11. Lihat Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 6 (mendefinisikan transisi sebagai interval antara satu rezim politik dengan rezim politik lainnya); Juan J. Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, dalam Fred I. Greenstein dan Nelson W. Polsby (eds.), Handbook of Political Science: Macropolitical Theory, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1975, Vol. III, 182-83. Untuk pandangan klasik tentang hal ini, lihat Robert Dahl, Polyarchy, New Haven: Yale University Press, 1971, 20-32, 74-80. Lihat juga Huntington, Third Wave, 7-8, Richard Gunther, et al., “O’Donnel’s ‘Illusions’: A Rejoinder”, Journal of Democracy 7, No.4 (1996), 151-53. 12. Lihat Huntington, Third Wave, 7. 13. Untuk kritik terhadap pandangan teleologis ini, lihat Guillermo O’Donnell, “Illusions and Conceptual Flaws”, Journal of Democracy 7, No. 4 (1996), 160, 163-64, dan Guillermo O’Donnell, “Illusions about Consolidation”, Journal of Democracy 7, No.2 (1996), 34. 14. Lihat umumnya Hertz, From Dictatorship to Democracy. 15. Observasi ini memiliki implikasi terhadap perdebatan-perdebatan tertentu dalam ilmu politik dan konstitusionalisme dan mungkin memiliki afinitas dengan perdebatan jurisprudensial tentang apa yang memberikan otoritas bagi hukum. Lihat Joseph Rae, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, New York: Oxford University Press, 1979, 214. 16. Yang dimaksud dengan “format legal” adalah prinsip, norma, ide, aturan, praktik dan juga badanbadan legislatif, administratif, ajudikasi dan penegakannya. Lihat Sally Falk Moore, Law as Process: An Anthropological Approach, Boston: Routledge, 1978, 54. Tentang signifikansi format legal, lihat Isaac D. Balbus, “Commodity Form and Legal Form: An Essay on the ‘Relative Autonomy’ of the Law”, Law and Society Review 11 (1977), 571-71. 17. Untuk pengantar pendekatan konstruktivistik, lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Anchor Books, Doubleday, 1966, 19 (menjelaskan pendekatan dari perspektif sosiologi). Tentang konstruktivisme dalam hukum, lihat Pierre Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal 38 (1987), 805, 814-40. Lihat juga Roberto Mangabeira Unger, False Necessity – Anti Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, New York: Cambridge University Press: 1987, 246-52 (menganalisis respon legal dan institusional dalam “perubahan konteks”). Untuk studi tentang peran hukum dalam membangun komunitas, lihat Robert Gordon, “Critical Legal Histories”, Stanford Law Review 36 (1984), 57. Lihat juga John Brigham, The Constitution of Interest: Beyond the Politics of Rights, New York: New York University Press, 1996 ( membicarakan peran hukum dalam membangun gerakan politik). 2 18. Lihat pada umumnya Dahl, Polyarchy; David Held, Models of Democracy, Stanford: Stanford University Press, 1987. Bab 1: Kedaulatan Hukum dalam Transisi 1. Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 1944, 72 , “[P]emerintah dalam semua tindakannya diikat oleh aturan yang ditetapkan dan diumumkan sebelumnya – aturan yang memungkinkan untuk meramalkan dengan penuh kepastian bagaimana pemegang kekuasaan akan menggunakan kekuasaannya dalam kondisi tertentu dan untuk merencanakan tindakan individual berdasarkan pada pengetahuan ini”.) Untuk pembicaraan tentang pemahaman umum mengenai peran kedaulatan hukum di negara-negara demokrasi sebagai batasan terhadap penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, lihat Roger Cotterell, The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy, Philadelphia: University of philadelphia Press, 1989, 113-14, yang menjelaskan bahayanya memandang negara sebagai entitas yang mengatasi hukum. Untuk penjelasan tentang kaitan antara hukum dengan demokrasi, lihat Jean Hampton, “Democracy and the Rule of Law,” dalam Nomos XXXVI: The Rule of Law, ed. Ian Saphiro, New York: New York University Press, 1995, 13. Penjelasan klasik tentang syarat minimum legalitas ditemukan dalam Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven: Yale University Press, 1964, 33-34. Ronald Dworkin menawarkan pemaparan kontemporer yang terpenting tentang teori kedaulatan hukum yang substantif. Lihat Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge: Harvard University Press, 1985, 11-12 (Dworkin berpandangan bahwa “konsepsi hak” dalam kedaulatan hukum mensyaratkan, sebagai bagian dari pandangan ideal tentang hukum, bahwa aturanaturan yang tertulis mencakup dan melaksanakan hak-hak moral). Lihat juga Frank Michelman, “Law’s Republic”, Yale Law Journal 97 (1988): 1493 (yang memaparkan interpretasi modern tentang pemerintahan oleh hukum melalui reinterpretasi teori politik republikanisme kemasyarakatan (civil republicanism). Margaret Jane Radin menggambarkan dasar filsafat dari pendekatan-pendekatan modern terhadap kedaulatan hukum dengan asumsi-asumsi berikut ini: (1) hukum tersusun atas aturan-aturan; (2) aturan berada di muka (sebelum) kasus-kasus khusus, lebih umum dari kasus-kasus khusus dan diterapkan terhadap kasus-kasus khusus; (3) hukum bersifat instrumental (aturan-aturan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya); (4) terdapat pemisahan radikal antara pemerintah dan warga negara (ada pemberi aturan dan pelaksananya, versus penerima aturan dan penaatnya); (5) manusia adalah pemilih yang rasional yang mengatur tindakan-tindakannya secara instrumental. Margaret Jane Radin, “Reconsidering the Rule of Law”, Boston University Law Review 69 (1989): 792. Lihat umumnya Cotterell, Politics of Jurisprudence (yang memberikan pengantar tentang perdebatan tentang sifat hukum); Allan C. Hutchinson dan Patrick Monahan (eds.), The Rule of Law, Toronto: Carswell, 1987 (yang mengumpulkan sejumlah esai tentang kedaulatan hukum); Roger Cotterell, “The Rule of Law in Corporate Society: Neumann, Kirchheimer, and the Lessons of Weimar”, Modern Law Review 51 (1988): 126-32 (tinjauan buku). 2. Untuk pembicaraan pengantar tentang tema-tema umum dalam konsep kedaulatan hukum dan konstitusionalisme, lihat A. V. Dicey, Introduction to the Study of Laws of the Constitution, Indianapolis: Libery Fund, 1982, 107-22. Lihat juga E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, New York: Pantheon Books, 1975. 3. Planned Parenthood v. Casey, 505 US 833, 854 (1992); Lihat Antonin Scalia, “The Rule of Law as the Law of Rules”, University of Chicago Law Review 56 (1989): 1175 (yang menyarankan “kedaulatan hukum umum” di atas “keinginan individual untuk berlaku adil”). 4. Lihat H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review 71 (1958); 593 (yang membela positivisme); Lon L. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law – A Reply to 3 Professor Hart”, Harvard Law Review 71 (1958): 630 (yang mengkritik Hart karena mengabaikan peran moralitas dalam pembentukan hukum). 5. Teori-teori lain tentang sifat kedaulatan hukum dalam karya-karya Franz Neumann dan Otto Kircheimer juga mengambil masa ini sebagai titik tolaknya. Lihat Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, Frankfurt am Main: Europäjsche Verlagsanshalt, 1977, 1933-44; Franz Neumann, The Rule of Law: Political Theory and the Legal System in Modern Society, Dover: Berg Publishers, 1986; William E. Scheuerman (ed.), The Rule of Law under Siege: Selected Essays of Franz L. Neumann and Otto Kirchheimer, Berkley: University of California Press, 1996. Untuk suatu eksposisi yang menarik tentang pandangan para pakar tersebut, lihat William E. Scheuermann, Between the Norms and the Exception: The Frankfurt School and the Rule of Law, Cambridge: MIT Press, 1994, yang mencoba menerapkan analisis Neumann dan Kirchheimer ke dalam negara kesejahteraan kapitalis abad ke-20. 6. Lihat “Recent Cases”, Harvard Law Review 64 (1951): 1005-06 (yang mengutip Jerman, Judgement of July 27, 1949, 5 Suddeutscher Juristen Zeitung (1950): 207 (Oberlandesgericht [OLG] [Bamberg]). 7. Lihat secara umum Fuller, Morality of Law, 245. 8. Untuk eksplorasi yang mendalam tentang arti positivisme hukum, lihat Frederick Schauer, “Fuller’s Internal Point of View”, Law and Philosophy 13 (1994): 285. 9. Lihat Fuller, “Positivism and Fidelity to Law”, 642-43, 657. 10. Lihat Fuller, Morality of Law, 96-97. 11. Lihat Fuller, ibid. Untuk pembicaraan tentang perdebatan positivisme-hukum kodrat, lihat Gustav Radbruch, Rechtphilosophie, Stuttgart: Koehler, 1956; Gustav Radbruch, “Die Erneurung des Rechts”, Die Wandlung 2 (1947): 8. Lihat juga Markus Dirk Dubber, “Judicial Positivism and Hitler’s Injustice”, tinjauan Ingo Muller, “Hitler’s Justice”, Columbia Law Review 93 (1993): 1807; Fuller, Morality of Law, 23. 12. Untuk tinjauan yang baik tentang perdebatan sejarah ini, lihat Stanley L. Paulson, “Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the ‘Positivist’ Thesis”, Law and Philosophy 13 (1994): 313. 13. Lihat Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”, 617-18. 14. Fuller, Morality of Law, 245. 15. Ibid. 16. Ibid., 648. 17. Lihat Zentenyi-Takacs Law: Law Concerning the Prosecutability of Offenses between December 21, 1944 and May 2, 1990 (Hungaria, 1991), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law of East and Central Europe 1 (1994): 131. Lihat juga Stephen Schulhofer et al., “Dilemmas of Justice”, East European Constitutional Law Review 1, No. 2 (1992); 17. 18. Lihat umumnya Zentenyi-Takacs Law. 19. Lihat Decision of Dec. 21, 1993 (Republik Ceko, Pengadilan Konstitutional, 1993) (arsip Center for the Study Constitusionalism in Eastern Europe, University of Chicago (mengesahkan Act on the Illegality of the Communist Regime and Resistance to It, Act No.198/1993 (1993). 20. Untuk pembicaraan tentang perdebatan statuta pembatasan waktu di Jerman, lihat Adalbert Rückerl, The Investigation of Nazi Crimes, 1945-1978: A Documentation, terj. Derek Rutter, Heidelberg, Karlsruhe: C. F. Muller, 1979, 53-55, 66-67. 21. Judgment of March 5, 1992, Magyar Kozlony, No.23/1992 (Hungaria, Pengadilan Konstitusional, 1992), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law of East and Central Europe 1 (1994): 136. 4 22. Ibid.,141. 23. Ibid.,141-42. 24. Ibid., 142. 25. Bandingkan Ingo Müller, Hitler’s Justice: The Courts of the Third Reich, Cambridge: Harvard University Press, 1991 68, 71-78, dengan Dubber, Judicial Positivism and Hitler’s Injustice, 1819-1820, 1825. Lihat juga Richard Weisberg, Vichy Law and the Holocaust in France, New York: New York University Press, 1996. Untuk diskusi yang kaya akan gagasan, lihat Simposium, “Nazis in the Courtroom: Lessons from the Conduct of Lawyers and Judges under the Laws of the Third Reich and Vichy France”, Brooklyn Law Review 61 (1995): 1142-45. Untuk diskusi tentang Afrika Selatan, lihat David Dyzenhaus, Hard Cases in Wicked Legal Systems: South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, New York: Oxford University Press, 1991, dan Stephen Ellman, In a Time of Trouble: Law and Liberty in South Africa’s State of Emergency, New York: Oxford University Press, 1992. Untuk pembicaraan tentang strategi interpretif badan pengadilan Amerika Latin, lihat Mark J. Osiel, “Dialogue with Dictators: Judicial Resistance in Argentina and Brazil”, Law and Social Inquiry 29 (1995): 481. 26. Untuk perbandingan yang luas tentang pendekatan Amerika dan Inggris, lihat Anthony J. Sebok, “Misunderstanding Positivism”, Michigan Law Review 93 (1995): 2055. Untuk analisis jurisprudensi di bawah rezim perbudakan, lihat Robert M. Cover, Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process, New Haven: Yale University Press, 1975, 26-29, 121-23. Untuk diskusi tentang jurisprudensi Nazi, lihat umumnya Muller, Hitler’s Justice. 27. Untuk tinjauan sejarah, lihat Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago: Uninersity of Chicago Press, 1960, 162-73. Untuk sejarah intelektual tentang Rechstaat Jerman, lihat Steven B. Smith, Hegel’s Critique of Liberalism, Chicago: University of Chicago Press, 1989, 145-48. 28. Untuk diskusi terkait tentang tirani dan hukum, lihat Judith N. Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials, Cambridge: Harvard University Press, 1964, 126-27. 29. Lihat Henry W. Ehrmann, Comparative Legal Cultures, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976, 48-50; James L. Gibson dan Gregory A. Caldeira, “The Legal Cultures of Europe”, Law and Society Review 30 (196): 55-62. 30. Untuk suatu pernyataan tentang syarat hukum demikian, lihat Fuller, “Positivism and Fidelity to Law”, 638-43. Lihat juga Joseph Raz, The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System, New York: Oxford University Press, 1970 (yang merupakan usaha sistematis untuk menjelaskan syarat-syarat hukum). 31. Judgment of Jan. 20, 1992, Juristenzeitung 13 (1992): 691, 695 (Jerman Barat, Landgreicht [LG], Berlin). 32. Lihat Raz, Concept of a Legal System, 214. 33. Lihat umumnya Bonaventura De Soisa Santos, Toward a New Common Sense: Law, Science, and Politics in the Paradigmatic Transition, New York: Routledge, 1995 (yang memaparkan teori hukum dengan merujuk pada kaitan hukum dan masyarakat yang dinamis). 34. Lihat Hans Kelsen, “The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of the Axis War Criminals”, Judge Advocate Journal (Musim Gugur-Dingin 1945): 8-12, 46 (yang membicarakan sifat jurisdiksi dalam Tribunal Nuremberg dan pengadilan pasca-perang lainnya); Bernard D. Meltzer, “A Note on Some Aspects of the Nuremberg Debate”, University of Chicago Law Review 14 (1947): 455-57. (“Penerapan secara kaku dan otomatis aturan melawan retroaktivitas pada sistem hukum yang belum berkembang [seperti hukum internasional] akan, tentu saja, memperlebar jurang atara perasaan moral yang berkembang di masyarakat dan institusi legalnya yang terbelakang”). Lihat umumnya Stanley L. Paulsen, “Classical Legal Positivism at Nuremberg”, Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 132 (yang menyatakan bahwa penolakan pembelaan Nazi oleh Tribunal Nuremberg dijustifikasikan oleh 5 penolakannya terhadap positivisme legal klasik); Quincy Wright, “Legal Positivism and the Nuremberg Judgment”, American Journal of International Law 42 (1948): 405 (menyatakan bahwa kritikan terhadap peradilan Nuremberg yang dianggap menerapkan hukum ex post facto berakar pada teori hukum internasional positivis yang dipegang para pengkritik tersebut). 35. Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka) 36. Lihat Act on Procedures Concerning Certain Crimes Committed during the 1956 Revolution, Hungaria, 1993 (arsip Center for the Study of Constitusionalism in Eastern Europe, University of Chicago). 37. Lihat “Geneva Convention Relative on the Protection of Civilian Persons in Time of War”, 12 Agustus 1949, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 75, No. 973 (1950); 287; “Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity”, 11 November 1970, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 754, No. 10823 (1970): 73. 38. Di Polandia, masalah statuta pembatasan waktu baru terselesaikan dengan konsensus konstitusional. Lihat Konstitusi Republik Polandia, Pasal 43 (yang disahkan Dewan Nasional, 2 April 1997), yang menyatakan bahwa sejauh suatu pelanggaran merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka tidak diikat oleh pembatasan waktu. 39. Resolution of the Hungarian Constitutional Court of Oct. 12, 1993 on the Justice Law (Kasus 53/1993) (arsip Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, semula di University of Chicago). Lihat Konstitusi Hungaria, Pasal 7 ayat 1 (“Sistem hukum Republik Hungaria ... menyesuaikan hukum nasional dan statuta negara dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional”). Bandingkan dengan Konstitusi Yunani, Pasal 28 ayat 1 (yang menyatakan bahwa kedaulatan hukum internasional diutamakan terhadap hukum domestik yang berlawanan). 40. Lihat Border Guards Prosecution Cases (Jerman Barat, Bundesgerichtshof [BGH]), diterjemahkan dalam International Law Reports 100 (1995): 380-82 (yang mempertimbangkan International Covenant on Civil and Political Rights, 19 Desember 1966, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 999, No. 14688 (1976): 171 (yang menyatakan bahwa ketertiban domestik melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh traktat internasional). Lihat umumnya Stephan Hobe dan Christian Tietje, “Government Criminality: The Judgement of the German Federal Constitutional Court of 24 October 1996”, German Yearbook of Internatioanal Law 39 (1996): 523. Lihat juga Krisztina Morvai, “Retroactive Justice Based on International Law: A Recent Decision by the Hungarian Constitutional Court”, East European Constitutional Review (musim gugur 1993/musim dingin 1994): 33; “Law on Genocide and Crimes against Humanity Committed in Albania during Communist Rule for Political, Ideological and Religious Motives”, diterjemahkan dalam Human Rights Watch, Human Rights in Post-Communist Albania, New York: Human Rights Watch, 1996, lampiran A (menjadi dasar untuk mengadili bekas Komunis). 41. Lihat Statute of the International Court of Justice, U. S. Statutes at Large 59 (1945): 1031, Pasal 38 (1). Untuk pembahasan tentang pemahaman positivis, lihat Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice, Dordrecht, Belanda; dan Boston: M. Nijhoff, 1991; didistribusikan di Amerika Serikat dan Kanada oleh Kluwer Academic Publishers), 35-36. Peran kebiasaan dalam pembentukan hukum internasional dijelaskan dalam Michael Akehurst, “Custom as a Source of International Law”, British Yearbook International 47 (1974-1975): 1. Untuk diskusi terkait tentang elemen-elemen hukum positif dan hukum kodrat dalam hukum internasional, lihat Shklar, Legalism: Law, Morals, and Political Trials, 126-28. 42. Lihat J. M. Balkin, “Nested Opposition”, Yale Law Journal 99 (1990): 1669 (tinjauan buku). 43. Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas), 693. 6 44. Lihat Decision of Dec. 21, 1993 (dikutip di catatan kaki 19 di atas). 45. Untuk tinjauan tentang sifat pengambilan keputusan demikian dalam sistem politik non-liberal, lihat diskusi tentang decisionism dalam Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, terjemahan George Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 1985, 53-66. 46. Untuk penjelasan tentang awal perkembangan ini, lihat Herman Schwartz, “The New East European Constitutional Courts”, Michigan Journal of International Law 13 (1992): 741. Lihat Ruti Teitel, “Post Communist Constitutionalism: A Transitional Perspective”, Columbia Human Rights Law Review 26 (1994): 167. Untuk kumpulan esai tentang pengadilan konstitusional Eropa Timur, lihat Irena GrudzinskaGross (ed.), Constitutionalism in East Central Europe, Bratislava: Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation, 1994. Lihat juga Konstitusi Afrika Selatan, Bab VII (dibicarakan pada bab tentang keadilan konstitusional dalam buku ini). 47. Lihat Judgment of Jan. 20, 1992 (dikutip di catatan kaki 31 di atas). 48. Lihat Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka). 49. Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 169-76. 50. Lihat Ethan Klingsberg, “Judicial Review and Hungary’s Transition from Communism to Democracy: The Constitutional Court, the Continuity of Law, and the Redefinition of Property Rights”, Brigham Young University Law Review 1992 (1992): 62 (membicarakan akses yang sangat terbuka yang ditimbulkan oleh aturan Hungaria yang sangat permisif). Negara tersebut bukanlah satu-satunya di wilayah tersebut yang memperimbangkan partisipasi para aktor politik dalam litigasi konstitusional. 51. Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism,” 186-87. 52. Lihat Judgment of March 5, 1992 (dikutip di catatan kaki 21 di muka). 53. Lihat R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press, 1977, 84. 54. Ibid., 84, 138. 55. Menyangkut paradigma tradisional tentang badan pengadilan, lihat umumnya Martin Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis, Chicago: University of Chicago Press, 1981. Lihat juga Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, New York: Clarendon Press, 1989, 31-34 (mengamati bahwa para hakim harus “membuat hukum” dengan menafsirkannya namun membedakan tugas ini dari tugas para legislator, yang bertindak dengan prosedur yang berbeda). Untuk pernyataan klasik tentang peran badan pengadilan dalam demokrasi, lihat umumnya Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch, New Haven: Yale University Press, 1986; Jesse H. Choper, Judicial Review and the National Political Process, Chicago: University of Chicago Press, 1980; dan John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge: Harvard University Press, 1980. 56. Pada awal pergeseran politik, parlemen transisional biasanya merupakan peninggalan dari masa represif sebelumnya. Lihat Andrew Arato, “Dilemmas Arising from the Power to Create Constitutions in Eastern Europe”, Cardozo Law Review 14 (1993): 674-75. 57. Untuk pembicaraan ilustratif tentang transisi Rusia menuju berkurangnya kekuasaan Negara, lihat Stephen Holmes, “Can Weak-State Liberalism Survive?” (makalah dipresentasikan di Colloquium tentang Teori Konstitusional di New York University School of Law, musim semi 1997, arsip penulis). 58. Lihat Teitel, “Post-Communist Constitutionalism”, 182-85. 59. Lihat misalnya Müller, Hitler’s Justice, 201 (membicarakan badan pengadilan yang terkompromi di Jerman pasca-perang). 60. Lihat misalnya Ronald M. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: Harvard University Press, Belknap Press, 1986; Bruce R. Douglass, Gerald M. Mara dan Henry S. Richardson (eds.), Liberalism and the Good, New York: Routledge, 1990. 7 61. Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition, New York: Harper and Row, 1978, 4-5; Richard L. Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, New York: Acdemic Press, 1982, 267; David M. Trubek, “Turning Away from Law?” Michigan Law Review 82 (1984): 825. 62. Untuk eksplorasi tentang berbagai pemikiran yang bertentangan mengenai kedaulatan hukum dari perspektif liberalisme dan teori hukum kritis, lihat umumnya Andrew Altman, Critical Legal Studies: A Liberal Critique, Princenton: Princenton University Press, 1990. Bab 2: Peradilan Pidana 1. Lihat Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press, [1769], 1995; Jeremi Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Vol. 2, Darien, Conn: Hafner Publishing [1823], 1970 (berteori bahwa hukuman diperlukan untuk kebaikan bersama). 2. Lihat Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, New York: Oxford University Press, 1979, 400-01. 3. Lihat David Lagomarsino dan Charles T. Wood, The Trial of Charles I: A Documentary History, Hanover, N.H: University Press of New England, 1989, 25; Michael Walzer (ed.), Regicide and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI, terjemahan Marian Rothstein, New York: Cambridge University Press, 1974, 88. 4. Untuk argumen kontemporer, lihat Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute, Human Rights Violations of a Prior Rezim”, Yale Law Journal 100 (1991): 2537. 5. Walzer (ed.), Regicide and Revolution, 88. 6. Ibid., 5. 7. Ibid., 78. 8. Judith N. Shklar, Legalism, Morals, and Political Trials, Cambridge: Harvard University Press, 1964, 145. 9. Otto Kirchheimer, Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, Wesport, Conn: Greenwood Press, 1961, 308. 10. Lihat Ruti Teitel, “How Are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” (makalah dipresentasikan sebagai latar belakang untuk diskusi di Council on Foreign Relations, mengkritik bahwa demokrasi menjustifikasi kewajiban untuk menghukum), New York, 17 Mei 1990. 11. Untuk tinjauan tentang pengadilan-pengadilan nasional yang gagal, lihat George Gordon Battle, “The Trials Before the Leipsic Supreme Court of Germans Accused of War Crimes”, Virginia Law Review 8 (1921): 1. 12. Komisi Persiapan Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah menyelesaikan tugasnya dengan mengesahkan kerangka kerja untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional. Lihat U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.6-18, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.21, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.19, U.N. doc. A/AC.249/1998/CRP.3/Rev.1. Hingga diterbitkannya buku ini [dalam versi Inggris, ed.], Sidang Diplomatik Tingkat Tinggi PBB untuk Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional telah bersidang di Roma antara 15 Juni sampai 17 Juli 1998, untuk memfinalkan dan menyetujui konvensi untuk pembentukan pengadilan tersebut. Lihat umumnya Cristopher Keith Hall, “The First Two Sessions of the U.N. Preparatory Commitee on the Establishment of an International Criminal Court”, American Journal of International Law 91 (1997): 177; James Crawford, “The ILC Adopts a Statute for an International Criminal Court, American Journal of International Law 89 (1995): 404 (membicarakan rancangan statuta Komisi Hukum International [ILC] untuk membentuk pengadilan pidana internasional); Bernhard Graefrath, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court”, European Journal of 8 International Law 1 (1990): 67 (membicarakan usaha PBB untuk membentuk pengadilan pidana internasional). [Mahkaham yang dimaksud itu, yaitu Mahkamah Pidana Internasional, saat ini telah didirikan, ed.] 13. Lihat Norman E. Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals and War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book, New York: Greenwood Press, 1986. 14. Lihat catatan kaki 12 di atas. 15. Sebuah contoh yang buruk adalah penolakan Amerika Serikat terhadap jurisdiksi Mahkamah Internasional dalam kasus yang diajukan Nikaragua. Lihat Nicaragua v. United States, 1984 ICJ 392 (1984). 16. Lihat Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, New York: Times Books, 1998. 17. Untuk komentator dengan posisi ini, lihat misalnya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York: Penguin Books, 1964. 18. PBB, Sidang Umum, International Law Commission: Report on the Principles of the Nuremberg Tribunal, Prinsip I, A/1316 (1950). 19. Ibid. Prinsip III dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seorang pelaku tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau pejabat pemerintahan yang bertanggung-jawab tidak melepaskannya dari tanggung jawab menurut hukum internasional.” 20. Baik Nuremberg maupun kasus lain sesudahnya, kasus Einsatzgruppen, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. 4-5 (Washington, DC: GPO, 1949-1953), menolak pembelaan kepatuhan pada perintah dan doktrin respondeat superior yang mengalihkan tanggung jawab pada pemberi perintah. Doktrin “tanggung jawab absolut” sebaliknya, yang menyatakan bahwa perintah atasan tidak pernah bisa menjadi justifikasi tindakan melanggar hukum, diajukan dalam Mitchell v.Harmony, 13 How 115 (1851) dan kemudian dimuat dalam Prinsip Nuremberg pada Pasal 8. Dalam standar ilegalitas yang diterima, jika seseorang yang bisa berpikir dengan baik bisa memahami bahwa perintah yang diterimanya secara manifes ilegal, maka pembelaan kepatuhan ini ditolak. Prinsip IV dari Prinsip Nuremberg menyatakan: “Fakta bahwa seseorang bertindak mengikuti perintah pemerintahnya atau atasannya tidak membebaskannya dari tanggung jawab menurut hukum internasional, dengan syarat bahwa ia bisa melakukan pilihan moral.” 21. Lihat Judgment in the Tokyo War Crimes Trial, 1948, dicetak ulang sebagian dalam Richard Falk, Gabriel Kolko dan Robert Jay Lifton (eds.), Crimes of War: A Legal, Political-Documentary, and Psychological Inquiry into the Responsibility of Leaders, Citizens, and Soldiers for Criminal Acts in Wars, New York: Ramdon House, 1971, 113. Jenderal Yamashita mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang mengafirmasi prinsip tersebut. Lihat In re Yamashita, 327 US I, 13-18 (1945). 22. United States v. Wilhelm von Leeb, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 462 (1950) (High Command Case); United Sates v. Wilhelm List, dicetak ulang dalam XI Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, 1230 (1950) (Hostage Case). 23. Lihat umumnya Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, Chicago: Quadrangle Books, 1970. Lihat juga Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 177-415. 24. Lihat United States v. Calley, 46 CMR 1131 (1973). Lihat juga Gary Kamarow, “Individual Responsibility under International Law: The Nuremberg Principles in Domestic Legal System”, International and Comparative Law Quarterly 29 (1980): 26-27, untuk diskusi singkat tentang kasus Calley dalam konteks ini. 9 25. Protokol I, “Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts”, 8 Juni 1977, Treaties and International Agreements Registered or Filed of Reported with the Secretariat of the United Nations 1125, No. 17512 (1979): 609. 26. Untuk diskusi ilmiah, lihat Theodor Meron, War Crimes Law Comes of Age: Essays, Oxford: Clarendon Press, 1998. 27. Lihat Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, New York: Knopf 1992. 28. Ibid. 29. Seperti Jaime Malamud-Goti, Game without End: State Terror and the Politics of Justice, Norman: University of Oklahoma, Press, 1996. 30. Helsinki Watch, War Crimes in Bosnia Hercegovina, Vol. I, New York: Human Rights Watch, 1992. (Laporan Helsinki Rights Watch). 31. Proceedings of Las Malvinas Trial (arsip penulis). 32. Lihat “Four Hardline Communists Investigated over 1968 Prague Invasion”, Reuters, 17 April 1990, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters; “August 1968 – Gateway to Power for Number of Politicians”, CTK National News Wire, 18 Agustus 1998, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK. 33. Act on the Illegality of the Communist Regime and Resistance to It, Act. No. 198/1993 (Republik Ceko, 1993). 34. Lihat “Velvet Justice for Traitors Who Crushed 1968 Prague Spring”, The Telegraph, Praha 23 Agustus 1998 (melaporkan ketiadaan sanksi bahkan setelah penyidikan delapan tahun). 35. Lihat “Polish Politicians Ask for Trial for Martial Law Instigators”, Reuters, 9 Desember 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga Tadiusz Olszaski, “Communism’s Last Rulers: Fury and Fate”, Warsaw Voice, 18 November 1992, tersedia di Lexis, News Library. Untuk kisah pengakuan Jeruzelski dan lain-lainnya, lihat RFE/RL Daily Report No. 49, 12 Maret 1993. Lihat juga “Walesa to Testify on Martial Law”, Polish News Bulletin, 25 Mei 1994, bagian politik. 36. Hingga terbitnya buku ini, Jeruzelski belum diadili karena alasan kesehatan. Lihat “Jeruzelski Will Not Be Tried”, Polish News Bulletin, 9 Juli 1997, bagian politik. Namun, terungkapnya dokumendokumen yang memberatkan mungkin akan memperkuat posisi pihak-pihak yang menginginkan pengadilan. Lihat “Constitutional Accountability Commision Meets”, Polish News Bulletin, 26 Oktober 1994; “Russian Dissident Accuses Jeruzelski”, Polish News Bulletin, 20 Mei 1998, bagian politik. Lihat juga Tad Szulc, “Unpleasant Truths about Eastern Europe”, Carnegie Endowment for International Peace, Foreign Policy, 22 Maret 1996, tersedia di Lexis, News Library. 37. Lihat Michael Shields, “Hungary Gets Ready to Try to Communist Villains of 1956”, Reuters, 5 November 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga Jane Perlez, “Hungarian Arrests Set off Debate: Should ’56 Oppressors be Punished?” New York Times, 3 April 1994, tersedia di Lexis, News Library. 38. Constitutional Court Decision on the Statute of Limitation, No. 2086/A/1991/14 (Hungaria, 1992). 39. Act on Procedures Concerning Certain Crimes Committed during the 1956 Revolution (Hungaria, 1993) (arsip Center for the Study of Constitutionalism in Eastern and Central Europe, University of Chicago). Pada tanggal 3 November 1993, diperintahkan penyelidikan terhadap pembantaian 1956, “atas kecurigaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan”. Sejak disahkannya hukum tersebut, penangkapan, pengadilan dan penuntutan telah berjalan. Lihat “Court Convicts Defendant for War Crimes in 1956 Uprising”, BBC Summary of World Broadcasts, 18 Januari 1997, tersedia di Lexis, News Library. Lihat 10 juga “Hungary Arrests More in 1956 Shootings Probe”, Reuters, 11 Februari 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 40. Lihat misalnya “United Nations Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects”, 10 Oktober 1980, Treaties and International Agreements Registered or Filed or Reported with the Secretariat of the United Nations 1342, No. 22495 (1983): 137; Protokol I, Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 Agustus 1949, Treaties and International Agreements Registered of Filed of Reported with the Secretariat of the United Nations 75, No. 973 (1950): 287. Untuk analisis mendalam, lihat Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, New York: Oxford University Press, 1989 (menjelaskan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik internasional dan internal). 41. Lihat Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. doc. A/Conf. 183/9. 17 Juli 1998, Pasal 7 (mendefinisikan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai bagian dari “kekerasan yang luas atau sistematis yang diarahkan kepada kelompok penduduk sipil apa pun”). Untuk ilustrasi, lihat umumnya Helsinki Watch, War Crimes in Bosnia-Hercegovina (melaporkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Balkan). Lihat Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Pasal 5, dilampirkan pada PBB, Sidang Umum, Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the U.N. Security Council Resolution 808, S/25704 (1993), dicetak ulang dalam International Legal Materials 32 (1993): 1159, 1193-97. Berbagai tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan, penindasan atas dasar politik, ras dan agama, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya”. Pemahaman Komisi Pakar adalah bahwa Tribunal Internasional memiliki jurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lihat PBB, Dewan Keamanan, Final Report of the Commission of Expert Established Pursuant to Security Council Resolution 780, S/1994/674 (1992), 13. Lihat juga Prosecutor v. Tadic, kasus No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 2 Oktober 1995), dicetak ulang dalam International Legal Materials 35 (1996): 32. Namun, sidang banding memberikan batasan terhadap interpretasi “pelanggaran berat” dan menekankan bahwa pelanggaran demikian yang merupakan jurisdiksi haruslah merupakan bagian dari konflik bersenjata internasional. Jurisdiksi tribunal mencakup kejahatan yang dilakukan bukan oleh agen negara, selama dilakukan “dengan pengaruh” negara. Statuta tribunal ini dimuat dalam PBB, Dewan Keamanan, Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of U.N. Security Council Resolution 808, (1993), dicetak ulang dalam International Legal Materials 32 (1993): 1159. Pasal 2 tentang kompetensi Tribunal Internasional menyatakan: “Tribunal internasional memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvnsi Jenewa 12 Agustus 1949”. Pasal tersebut kemudian memberikan rincian pelanggaran. Pasal 7 mendefinisikan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai bagian dari “kekerasan yang luas atau sistematis yang diarahkan kepada kelompok penduduk sipil apa pun”. 42. Sebagai contoh, Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di Yugoslavia nyaris sejak dimulainya konflik, menerbitkan catatan yang mendetail dan menyerukan pengadilan terhadap kejahatan perang. Lihat Helsinki, War Crimes in Bosnia-Hercegovina, Vol.1 dan 2. 43. Lihat umumnya Arnold J. Toynbee, Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, New York: Tankian, 1975. Lihat juga Dickran Boyajian, Armenia: The Case for a Forgotten Genocide, Wesrwood, N.J: Educational Book Crafters, 1972. 44. Lihat Symposium, “1945-1995 Critical Perspectives of the Nuremberg Trials and State Acountability”, New York Law School Journal of Human Rights 12 (1995): 453; Inge S. Neumann, European War Crimes Trials, ed., Robert A. Rosenbaum, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1951. Lihat umumnya Randolph L. Braham (ed.), Genocide and Retribution, Boston: Kluwer-Nijhoff, 1983. Untuk daftar bibliografi lengkap, lihat umumnya Tutorow (ed.), War Crimes, War Criminals, and War Crimes Trials; Neumann, European War Crimes Trials. Lihat juga Owen M. Kupferschmid Holocaust and 11 Human Rights Project Seventh International Conference, “Judgements on Nuremberg: The Past Half Century and Beyond – A Pannel Discussion of Nuremberg Prosecutors”, Boston College Third World Law Journal 16 (1996): 1993; Symposium, “Holocaust and Human Rights Law: The Fourth International Conference”, Boston College Third World Law Journal 12 (1992): 1. 45. Lihat Adalbert Rückerl, The Investigation of Nazi Crimes: 1945-1978: A Documentation, terjemahan Derek Rutter (Heidelberg, Karlsruhe4: C.F. Müller, 1979). Lihat “5,570 Cases of Suspected Nazi Crimes Remain Open,” This Week in Germany, 3 Mei 1996 (melaporkan bahwa 106.178 orang telah diadili dan 6.494 diputuskan hukumannya). 46. Mengenai pengadilan Klaus Narbie, lihat misalnya, Féderation Nationale des Déportés es Internés Réesitstant et Patriotes v. Barbie, 78 ILR 125 (Fr. Cass. Crim., 1985). Pengadilan Paul Touvier untuk kejahatan terhadap kemanusiaan diakhiri dengan hukuman seumur hidup. Lihat Alam Riding, “Frenchman Convicted of Crimes against the Jews in ’44,” New York Times, 20 April 1994, Sec. A3; Judgment of Apr. 20, 1994, Cour d’assises des Yvelines. Maurice Papon, dalam usia 87 tahun, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas perannya dalam deportasi warga Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Tuduhan lain tentang kejahatan terhadap kemanusiaan diajukan kepada Jean Leguay dan Rene Bousquet, namun keduanya meninggal dunia selama proses berjalan. Judgment of Oct. 21, 1982, Cass. Crim. Lihat Bernard Lambert, Bousquet, Papon, Touvier, Inculpés de Crimes contre I’humanite: Dossiers d’accusation (Paris: Federation Nationale des Déportés es Internés Résistants et Patriotes). 47. Lihat Timothy L.H. McCormack dan Jerry J. Simpsons, “The International Law Commission’s Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind: An Appraisal of the Substantive Provisions”, Criminal Law Forum 4 (1994): 1; Ronnie Edelman et al., “Prosecuting World War II Prosecutors: Efforts at an Era’s End”, Boston College Third World Law Journal 12 (1992): 199. 48. Untuk pembicaraan tentang pengadilan Yunani, lihat Nikiforos Diamandouros, “Regime Change and the Prospects of Democracy in Greece: 1974-1983, dalam Guillermo O’Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perpectives, Baltimore: Johns Hpokins University Press, 1991, 138. Untuk pembicaraan tentang transisi Portugal, lihat Kenneth Maxwel, “Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal”, dalam Guillermo O’Donnel et al. (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991, 109-37. Lihat juga John H. Herz (eds.), From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Wesport: Conn: Greenwood Press, 1982. 49. Lihat misalnya Border Guards Prosecution Case, International Law Reports 100 (1995): 366, 30. Untuk pembicaraan tentang beberapa dari kasus tersebut, lihat Stephan Hobe dan Christian Tietje, “Government Criminality: The Judgment of the German Federal Constitutional Court of 14 October 1996”, German Yearbook of International Law 39 (1996): 523. Untuk tinjauan jurnalistik komparatif tentang berbagai respon di wilayah tersebut, lihat Tina Rosenberg, The Hounted Land, New York: Random House, 1996. 50. Lihat “Symposium, 1945-1995 Critical Perspectives on the Nuremberg Trials and State Accountability,” New York Law Shool Journal of Human Rifhts 12 (1995): 453 (tinjauan tentang pengadilan Etiophia). 51. Lihat “Trial of 51 on Rwanda Genocide Charges Opens in Byumba”, Agence France-Presse (Kigali), 18 Maret 1998. Lihat juga Payam Alchavan, “The International Criminal Court Tribunal For Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment”, American Journal of International Law 90 (1996): 501. 52. Untuk argumen mendukung pengadilan selektif, lihat Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rughts Violations of a Prior Regime”, Yale Law Journal 100 (1991): 2537. Lihat juga Guillermo O’Donnel dan Phillipe C. Schmitter, Transitions from Authiritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986, 29-30 (membicarakan pengadilan selektif di Yunani. 12 53. Lihat H.L.A, Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford: Clarendon Press, 1968. 54. Untuk eksplorasi terhadap beberapa dari pertanyaan tersebut, lihat Sanford Levinson, “Responsibility for Crimes of War”, dalam Marshall Cohen et al. (eds.), War and Moral Responsibility, Princenton: Princenton University Press, 1974, 104; Richard Wasserstrom, “The Responsibility of the Individual for War Crimes”, dalam Virginia Held et al. (eds.), Philosophy, Morality, and International Affairs, New York: Oxford University Press, 1974, 47. Lihat juga Dennis F. Thompson, “Criminal Responsibility in Government”, dalam Roland Pennock dan John W. (eds.), Chapman Criminal Justice: Nomos XXVII, New York: New York University Press, 1985, 201-40. 55. Constitutional Court Decision on the Statute of Limitations, No. 2086/A/1991/14 (Hungaria, 1992), diterjemahkan dalam Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe 1 (1994): 129, 136. Lihat Konstitusi Republik Polandia, Pasal 43. 56. Sebelum diadili untuk kasus pembunuhan, Alexandru Draghici melarikan diri ke Hungaria, yang menolak mengekstradisinya, dengan mengutip statuta pembatasan waktu 30 tahun. Lihat “Romanian Court Delays Trial of Ex-Securitate Boss”, Reuters, 28 Juni 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 57. Pada bulan November 1991, parlemen Polandia mencabut statuta pembatasan waktu bagi kejahatankejahatan yang dilakukan antara tahun 1946 dan 1952 untuk memungkinkan pengadilan pidana baru. Lihat “Former Security Officers Go to Trial for Torturing Prisoners”, UPI, 13 Oktober 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip UPI. 58. Law on the Illegality of the Communist Regime, Act No. 198/1993 (Republik Federal Ceko dan Slowakia, 1993). 59. Lihat, “Erich Mielke Sentenced to Six Years for 1931 Murders: Faces Other Charges,” This Week in Germany, 29 Oktober 1993, 2. 60. Lihat Adrian Dascalu, “Romania Jails Eight for 1989 Timisoara Uprising Massacre,” Reuters, 9 Desember 1991, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 61. Miroslav Stepan, mantan ketua partai komunis Praha, diadili dan divonis pada tahun 1990. Lihat “Prague’s Ex-Party Boss Guilty of Abuse of Power”, Chicago Tribune, 10 Juli 1990, § 1, hlm. 4. Para menteri dalam negeri – Frantisek Kinel, Alojz Lorene dan Karel Vykypel – divonis pada bulan Oktober 1992. Lihat “Czechs Allow Prosecution of Communist Crimes”, Reuters, 10 Juli 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Lihat juga “August 1998 – Gateway to Power for Number of Politicians”, CTK National News Wire, 18 Agustus 1998, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK. 62. Lihat Howard Witt, “Russians Whitewash Blame for 1991 Coup”, Chicago Tribune, 12 Agustus 1994, § 1, hlm. 1. Apa yang semula dikoar-koarkan sebagai “pengadilan abad ini” ketika dimulai pada bulan April 1993, berakhir dengan pembebasan salah satu tertuduh yang menolak menerima amnesti Februari 1994, dan menuntut namanya dibersihkan. 63. Lihat “Ousted Bulgarian Gets 7-Year Term for Embezzlement”, New York Times, 5 September 1992, hlm. A2. Lihat juga “Bulgarian Former Prime Minister Sentenced to Ten Years”, Reuters, 3 November 1992, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. Namun, mahkamah agung negara tersebut membatalkan vonis tujuh tahun tersebut dan membebaskan Zhivkov pada tahun 1996. Lihat U.S. Department of State, Human Rights Country Reports (1997). 64. Lihat “Last Communist President Jailed for Five Years”, Agence France-Presse, 2 Juli 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Curnws. 65. Lihat “Former German Labor Boss Convicted of Fraud, Released”, Washington Post, 7 Juni 1991, hlm. A18. 13 66. Lihat misalnya, “Czech Republic: Slovakia Asked about Communist’s Tax Exemption”, Reuters, 30 Januari 1995, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 67. Yuri Feofanov, “The Estabilishment of the Constitutional Court in Rusia and the Communist Party Case”, Review of Central and East European Law 19, No. 6 (1993): 623-37. Untuk transkrip dalam bahasa Inggris tentang konferensi pers di mana para penuntut menjelaskan tujuan dan strategi hukum pengadilan, lihat Official Kremlin International News Broadcast, 6 Juli 1992, tersedia di Lexis, News Library. Untuk laporan jurnalistik, lihat David Remnick, “The Trial of the Old Regime”, New Yorker, 30 November 1992, hlm. 104. 68. Lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 35-36. Namun, pada akhirnya ada pergeseran ke proses administratif. Lihat bab 5. 69. Proclamation Establishing the Office of Special Prosecutor, pembukaan, No. 22/1992 (Ethiopia, 1992). 70. Di kalangan para analis hak asasi manusia, pengadilan “para penyiksa” Yunani dianggap sebagai model ideal pengadilan suksesor. Lihat Orentlicher, “Settling Accounts”, 2598. Untuk tinjauan mendetail tentang Pengadilan militer Yunani, Lihat Amnesty International, Torture in Greece: The First Torturer’s Trial, 1975, London: Amnesty International, 1877. Untuk pembicaraan tentang pengadilan selektif Yunani, lihat O’Donnell dan Schmitter, Transitions: Tentative Conclusions, 29-30. 71. Rückerl, Investigation of Nazi Crimes, 48, 137. 72. Lihat Judgment of Jan. 20, 1992, Juristenzeitung 13 (1992): 691, 692 (F.R.G. Landgericht [LG] [Berlin]), Stephen Kinzer, “2 East German Guards Convicted of Killing Man as He Fled to West”, New York Times, 21 Januari 1992, rubrik internasional. 73. Meskipun mantan pemimpin komunis, Egon Krenz dan ideolog partai Kirt Hager juga menjadi tertuduh, sukar untuk mendapatkan bukti yang mengaitkan mereka dengan penembakan. Willi Stoph, mantan perdana menteri, dan Erich Mielke, mantan kepala polisi rahasia, dibebaskan dari pengadilan karena alasan kesehatan. Lihat Stephen Kinzer, “Germany Frees Ailing Honecker, Who Flies to Chile”, New York Times, 14 Januari 1993, rubrik internasional. Tuntutan terhadap Honecker kemudian dibatalkan. Streletz, Albrecht dan Kessler, didakwa pada tanggal 16 September 1993, tetapi kemudian dibebaskan dari penjara karena alasan kesehatan. Lihat Rick Atkinson, “3 Ex-East German Officials Sentenced: Former Top Communists Found Guilty in Deaths of Refugees”, Washington Post, 17 September 1993; Leon Mangasarian, “East German Leaders Found Guilty of Wall Killings but Set Free, UPI, 16 September 1993, tersedia di Lexis, News Library, arsip UPI. Egon Krenz diadili bersama lima anggota politbiro lainnya atas tuduhan pembunuhan dalam peristiwa Tembok Berlin. Krenz dijatuhi vonis pada bulan Agustus 1997 untuk enam setengah tahun penjara. Dua pejabat tinggi politbiro lainnya masing masing dihukum tiga tahun. Lihat “Senior East German Officers Jailed for Berlin Wall Killings”, Deutscher Presse Agentur, 26 Maret 1998, tersedia di Lexis, News Library. “Hingga tahun 1997, terdapat 50 kasus yang dibawa ke pengadilan terhadap sekitar 100 serdadu, perwira dan pejabat pemerintah yang dituduh berkaitan penembakan di Tembok Berlin. Dari jumlah itu, 55 telah mendapatkan vonis. Hampir semua mendapatkan hukuman yang singkat atau ditunda. Edmund Andrews, “Honecker’s Succesor Jailed for Wall Killings”, International Herald Tribune, 26 Agustus 1997, tersedia di Lexis, News Library. Untuk diskusi doktrinal tentang kasus-kasus ini, lihat German Yearbook of International Law 36 (Berlin, 1993): 41. Untuk laporan jurnalistik, lihat Rosenberg, Haunted Land. 74. Proses peradilan terhadap Jorge R. Videla et al. semula diajukan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mengikuti Dekrit No. 158. Judgment of December 9, 1986 bagian 308-314 (Federal Criminal and Correctional Court of Appeals, Federal District of Buenos Aires), sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Alejandro M. Garro dan Henry Dahl, “Legal Accountability of Human Rights Violations in Argentina: One Step Forward and Two Steps Backward”, Human Rights Law Journal 8 (1978): 417-18. Lihat Paula K. Speck, The Trial of Argentine Junta: Responsibilities and Realities,” InterAmerican Law Review 18 (1987): 491. 14 75. Judgment of December 30, 1986 bagian 23-29, 48-49 (Mahkamah Agung Argentina, Buenos Aires). Sebagaimana diterjemahkan dan dicetak ulang dalam Garro dan Dahl, “Legal Accountability for Human Rights Violations in Argentina,” 435-39. 76. Untuk tinjauan tentang bagaimana militer menyatukan kekuatan untuk melawan ancaman hukuman, lihat Jaime Malamud-Goti, “Trying Violators of Human Rights: The Dilemma of Transitional Democratic Governments”, dalam State Crimes: Punishment of Pardon, Queenstown, Md: Aspen Institute, 1989, 7188. 77. Lihat John Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, 1985. 78. Lihat § 155 (II) StPO (pengadilan diwajibkan bertindak secara independen). Lihat German Code of Criminal Procedure, Vol. 10 (C), “Principles of Proof”, John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure: Germany, St. Paul: West Publishing, 1977. 79. Lihat Sheldon Glueck, War Criminals: Their Prosecution and Punishment, New York: Knopf, 1944, 19-36, untuk tinjauan sejarah tentang tindakan yang diambil terhadap penjahat perang Jerman menurut Perjanjian Versailles. Lihat juga James P. Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing War Criminals of the First World War, Westport, Conn: Greenwood Press, 1982, 116-39, 17476 (membicarakan usaha penghukuman pasca-Perang Dunia Pertama). 80. Lihat Frank M. Buscher, The U.S. War Crimes Trial Program in Germany, 1946-1955, New York: Greenwood Publishing Group, 1989, 62-64. 81. Lihat umumnya Herz (ed.), From Dictatorship to Democracy. 82. Amnesty Internasional, Torture in Greece, 65. Diamandouros, “Regime Change and the Prospects for Democracy in Greece: 1974-1983”, 138-64, 161. 83. Lihat “Argentine Seeks Rights-Trial Curb: Alfonsin Urges a Time Limit on Prosecution for Abuses under Military Rule”, New York Times, 6 Desember 1986, rubrik internasional. Lihat juga “200 Military Officers Are Pardoned in Argentina”, New York Times, 8 Oktober 1989, rubrik internasional, hlm. 12. Tentang gelombang kedua pemberian pengampunan, lihat Shirley Cristian, “In Echo of the ‘Dirty War’ Argentines Fight Pardons”, New York Times, 28 Desember 1990, rubrik internasional, hlm. A3. Lihat juga Americas Watch, Truth and Justice in Argentina: An Update, New York: Human Rights Watch, 1991; Carlos Nino, “The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina”, Yale Law Journal 100 (1991): 1619. Perkembangan terakhir di Argentina bertentangan dengan gejala ini. Lihat “President Says He Won’t Veto Repeal of Amnesty Laws”, Agence France-Presse, Buenos Aires, 26 Maret 1998; Marcela Valente, “Rights-Argentina: Dissatisfaction with Repeal of Amnesty Laws”, Inter Press Service, Buenos Aires, 25 Maret 1998. 84. Untuk tinjauan tentang kasus penjaga perbatasan, lihat Micah Goodman, “After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany”, Cornell International Law Journal 29 (1996): 727. Lihat juga “Former Albanian President Has Sentence Cut by Three Years”, Agence France Presse, 30 November 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip AFP; Henry Kamm, “President of Albania Rebuffed on Charter”, New York Times, 1 Desember 1994, tersedia di Lexis, News Library; “28 Communist Officials Tried for Antoconstitutional Activity”, CTK National News Wire, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip CTK (vonis terhadap mantan menteri keuangan Cekoslowakia Zak dan Ler); “Romanians Protest over Communist Bosses Release”, Reuters World Service, 21 September 1994, tersedia di Lexis, News Library, arsip Reuters. 85. Lihat Human Rights Watch Americas, Unsettled Business: Human Rights in Chile at the Start of the FREI Presidency, New York: Human Rights Watch, 1994, 1-4. 86. Lihat Azanian Peoples Organisation (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa and Others, 1996 (8) BCLR 1015 (CC) (menjunjung konstitusionalitas undang-undang amnesti); Lourens 15 du Plessis, “Amnesty and Transition in South Africa”, dalam Alex Boraine et al. (eds.), Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, Cape Town: Institute for Democracy in South Africa, 1994. 87. Tribunal tersebut dibentuk untuk tujuan “pengadilan terhadap orang-orang yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Lihat Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of the U.N. Security Council Resolution 808, S/25704 (1993). 88. Lihat International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia Since 1991: Rules for Procedure and Evidence, aturan 61, dicetak ulang dalam International Legal Materials 33 (1994): 519. Istilah superindictment digunakan untuk kepentingan internal tribunal. Lihat Graham Blewitt, wakil penuntut untuk Tribunal Yugoslavia, wawancara dengan penulis, Waldorf Astoria Hotel, New York, 7 April 1995. 89. Lihat Joel Feinberg, Doing and Deserving – Essays in the Theory of Responsibility, Priceton: Princeton University Press, 1970. Lihat juga Joel Feinberg, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, New York: Oxford University Press, 1084. 90. Lihat Oxford English Dictionary, edisi kedua, pada entri “prosecution”. 91. Lihat Sanford H. Kadish, “Foreword: The Criminal Law and the Luck of the Draw”, Journal of Criminal Law and Criminology 84 (musim dingin/semi 1994): 679, 698. 92. Lihat umumnya Hart, Punishment and Responsibility. 93. Untuk diskusi tentang kaitan peradilan pidana internasional dengan perdamaian dalam konteks konflik Balkan, lihat Ruti Teitel, “Judgment at the Hague”, East European Constitutional Review 5, No. 4 (musim gugur 1996). 94. Lihat Elaine Sciolino, “U.S. Names Figures to Be Prosecuted over War Crimes”, New York Times, 17 Desember 1992, rubrik internasional; Roger Cohen, U.N. in Bosnia, Black Robes Clash with Blue Hats”, New York Times, 23 April 1995, hlm. A3. 95. Lihat Jacques Dumas, Les Sanctiones Penales des Crimes Allemands, Paris: Rousseau et cie., 1916. 96. “The Moscow Declaration on German Atrocities, 1943”, dicetak ulang dalam Falk, Kolko dan Lifton (eds.), Crimes of War, 73. 97. Untuk tinjauan tentang usaha keras untuk mengajukan tuntutan tentang perang agresif, lihat Taylor, Anatomy of the Nuremberg Trials, 37-39. 98. Lihat Aristoteles, The Athenian Constitution, diterjemahkan dengan pengantar dan catatan oleh P.J. Rhodes, Harmondsworth: Penguin, 1984, bab 34-41-1. 99. Lihat José Maria Maravall dan Julian Santamaria, “Political Change in Spain and the Prospects for Democracy”, dalam Guillermo O’Donnell et al. (eds.), Transition from Authoritarian Rule: Southern Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991, 71-108. Lihat umumnya Raymond Carr dan Juan Pablo Aizpurtía, Spain: Dictatorship to Democracy, edisi kedua, London: Allen and Unwin, 1981. Untuk pembelaan terhadap amnesti Spanyol, lihat Fernando Rodrigo, “The Politics of Reconciliation in Spain’s Transition to Democracy” (makalah dipresentasikan pada Conference on Justice in Times of Transition, Salzburg, Maret 1993). 100. Tentang El Salvador dan Uruguay, lihat catatan kaki 103. Tentang Haiti, lihat Le Moniteur, Journal Offociel de la Republique d’Haiti Order (Arrète) of 2/6/90, yang memberikan amnesti total dan sepenuhnya kepada mereka yang antara 17 September 1988 dan 7 Februari 1990 terlibat dalam kejahatan dan pelanggaran terhadap keamanan nasional. Tentang amnesti Kolombia, lihat Javier Correa, “La 16 Historia de las Amnistias y los Indultos: Volver a Empezar”, dalam Los Cominos de la Guerra y la Paz, Vol. 1 La Reinsercìon, Bogotá: Fondo Editorial Para la Paz, 1990. 101. Lihat Howard W. French, “In Salvador, Amnesty vs. Punishment”, New York Times, 16 Maret 1993, rubrik internasional; Howard W. French, “Offer of Amnesty Removes Obstacle to Accord in Haiti”, New York Times, 14 April 1993, rubrik internasional. 102. Lihat “The Deal: Amnesty Law Expected to Clear Junta Very Soon”, New York Times, 21 September 1994, hal. A17. 103. Keputusan legislatif No. 486, 3/22/93, El Salvador (22 Maret 1993), menyetujui Undang-Undang Amnesti Umum untuk Konsolidasi Perdamaian. Lihat Todd Howland, “Salvador Peace Starts with Misstep”, Christian Science Monitor, 7 Februari 1992. John J. Moore Jr., “Problems with Forgiveness: Granting Amnesty under the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador”, Stanford Law Review 43 (1991): 733. “Ley de Reconciliacion Nacional” (Undang-undang Rekonsiliasi Nasional), Keputusan No. 145-96 tertanggal 23 Desember 1996, dicetak ulang dalam Guatemala Constitutional Court Decision on Amnesty, Nos. 8-97 and 20-97, at. 19-20 (7 Oktober 1997), instrumen dasar untuk rekonsiliasi dengan orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, dengan menghapuskan semua tanggung jawab pidana bagi kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam konflik bersenjata; dan menghapuskan tanggung jawab untuk kejahatan lainnya, terkecuali genosida, penyiksaan, atau penghilangan paksa. 104. Lihat Law No. 15.848 (Uruguay), “Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado (UndangUndang yang Menghapuskan Klaim Negara untuk Menghukum Kejahatan Tertentu), Pasal 1. Disepakati bahwa, sebagai konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang timbul dari persetujuan antara partai-partai politik dan angkatan bersenjata yang ditandatangani pada bulan Agustus 1984, dan untuk menyelesaikan transisi ke tatanan konstitusional sepenuhnya, negara mencabut haknya untuk memidana kejahatankejahatan yang dilakukan hingga tanggal 1 Maret 1985, oleh anggota militer atau polisi atas alasan politik atau memenuhi tugas dan menaati perintah dari atasan selama masa de facto; Americas Watch, Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and the Referendum Campaign in Uruguay, New York: Human Rights Watch, 1990. Lihat juga Shirley Christian, “Uruguay Votes to Retain Amnesty for the Military, New York Times, 17 April 1989, rubrik internasional, hlm. A8; Martin Weinstein, UruguayDemocracy at the Crossroads, Boulder: Westview Press, 1984. 105. Lihat Due Obedience Law; Law No. 23.049 (Argentina, 1984). The Full Stop Law; Law No. 23.492, diberlakukan pada tanggal 24 Desember 1986, dan Due Obedience Law; Law No. 23.523, diberlakukan pada tanggal 8 Juni 1987. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, melalui keputusan presiden, Pardon No. 1002 (7 Oktober 1989) memerintahkan bahwa semua proses hukum yang dijalankan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dihentikan. 106. Lihat umumnya Jonathan Truman Dorris, Pardon and Amnesty under Lincoln and Johnson: The Restoration of the Confederates to Their Rights and Privileges, 1861-1898, Westport, Conn: Greenwood Press [1953], 1977. 107. Lihat Konstitusi Sementara Afrika Selatan (1993) Epilogue on National Unity and Reconsiliation. Lihat § 20(2)(c) Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, seperti diperbaiki dalam Promotion of National Unity and Reconciliation Act 87 of 1995. Komisi harus memutuskan apakah suatu pelanggaran tertentu dapat dikaitkan dengan sasaran politik sesuai definisi dengan dasar apakah pelanggaran tersebut disarankan, direncanakan, diarahkan, diperintahkan, atau dilakukan di Afrika Selatan antara bulan Maret 1960 hingga Desember 1994, oleh atau atas nama organisasi politik yang dikenal secara publik, gerakan pembebasan, agen negara atau anggota pasukan keamanan, dan dengan melihat pada kriteria khusus yang dijabarkan dalam Reconciliation Act. Kriteria tersebut mencakup penyidikan terhadap motif, konteks, bobot dan tujuan dilakukannya pelanggaran, apakah pelanggaran tersebuit dilakukan atas perintah langsung atau persetujuan, dan apakah pelanggaran tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau “masalah pribadi, permusuhan atau rasa benci terhadap korban”, § 20(3)(f)(ii). 17 Lihat umumnya Allister Sparks, Tommorow is Another Country: The Inside Story of South Africa’s Road to Change, New York: Hill and Wang, 1995. 108. Untuk argumen utama yang menentang amnesti yang menyertai gelombang transisi kontemporer ini, lihat Aryeh Neier, “What Sould Be Done about the Guilty”? New York Review of Books, 1 Februari 1990, hlm. 32. 109. Lihat Stephen Holmes, “Making Sense of Postcommunism” (rancangan untuk New York University Program for the Study of Law, Philosophy and Social Theory), 10-13; Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991. 110. Lihat Orentlicher, “Settling Accounts”, 2537; Naomi Roth-Arriaza, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law”, California Law Review 78 (1990): 449. 111. Lihat Velásques-Rodrígues Judgment, Inter-Am. Ct. H.R., Ser. C., No. 4 (1988). 112. Lihat Report No. 28/92, Cases 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309, 10.311, Argentina’s Annual Report of the Inter-American Commision of Human Rights 1992-1993, 41b, OAS doc. OES/Ser.4L/UV/II.83/doc. 14/Corr. 1 (1993). Lihat juga Robert Goldman, “Amnesty Laws, International Laws, and the American Convention on Human Rights”, The Law Group Docket 6, No. 1 (1989): 1. 113. Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, terjemahan Mary Gregor, New York: Cambridge University Press, 1991, 183. 114. Lihat Teitel, “How are the New Democracies of the Southern Cone Dealing with the Legacy of Past Human Rights Abuses?” Namun ada pula pakar yang mendasarkan justifikasi untuk kebijakan pengampunan dengan pertimbangan retributif yang berdasar pada ketiadaan hukuman. Lihat Katherine Dean Moore, Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest, New York: Oxford University Press, 1989. 115. Lihat John Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Tradition of Western Europe and Latin America, Stanford: Stanford University Press, 1985; William T. Pizzi, “Understanding Prosecutorial Discretion in the United States: The Limits of Comparative Criminal Procedure as an Instrument of Reform”, Ohio State Law Journal 54 (1993): 1325. 116. Lihat Moore, Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest 790-86; “The Conditional Presiden Pardon”, Stanford Law Review 28 (1975): 149; Daniel T. Kobil, “The Quality of Mercy Strained: Wrestling the Pardoning Power from the King”, Texas Law Review 69 (1991): 569. 117. Lihat Irwin P. Stotzky (ed.), Transition to Democracy in Latin Amerikca: The Role of the Judiciary, Boulder: Westview Press, 1993. 118. Lihat Jeffrie G. Murphy dan