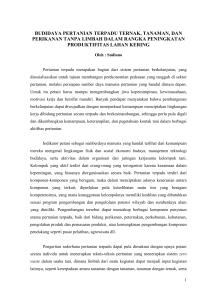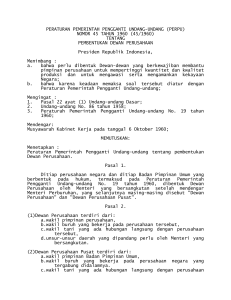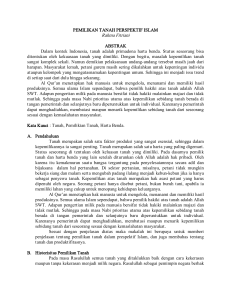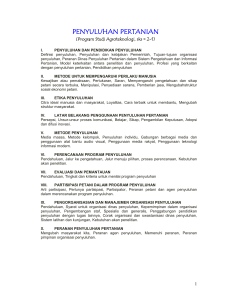tanah, pertanian dan pemiskinan petani
advertisement
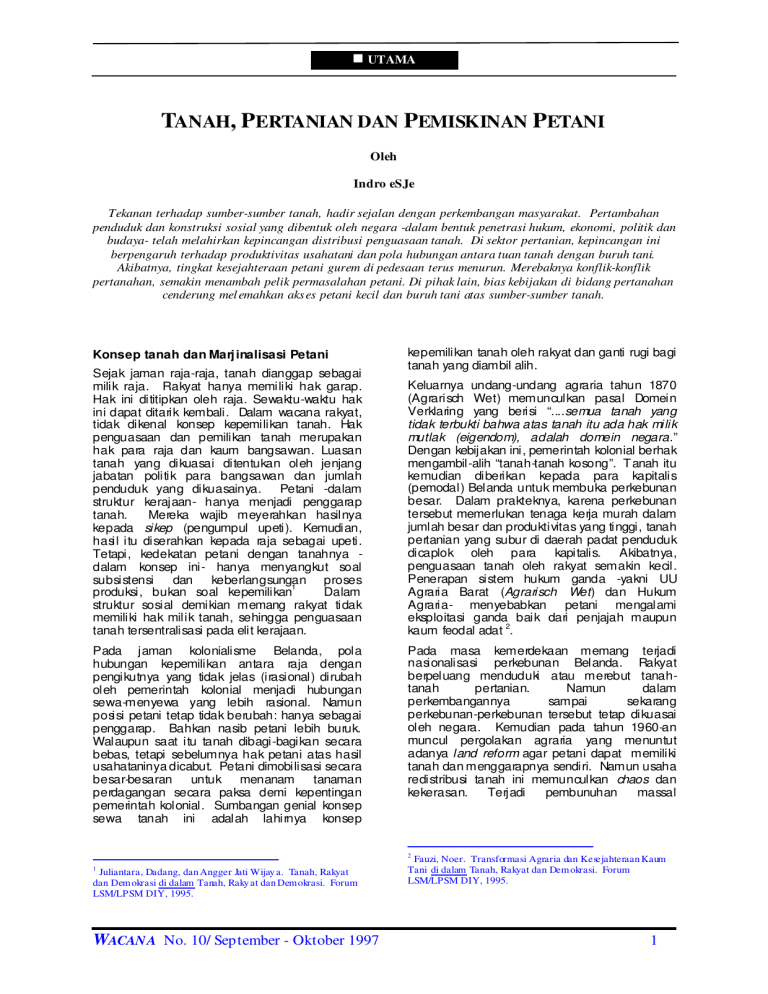
UTAMA TANAH, PERTANIAN DAN PEMISKINAN PETANI Oleh Indro eSJe Tekanan terhadap sumber-sumber tanah, hadir sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pertambahan penduduk dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh negara -dalam bentuk penetrasi hukum, ekonomi, politik dan budaya- telah melahirkan kepincangan distribusi penguasaan tanah. Di sektor pertanian, kepincangan ini berpengaruh terhadap produktivitas usahatani dan pola hubungan antara tuan tanah dengan buruh tani. Akibatnya, tingkat kesejahteraan petani gurem di pedesaan terus menurun. Merebaknya konflik-konflik pertanahan, semakin menambah pelik permasalahan petani. Di pihak lain, bias kebijakan di bidang pertanahan cenderung mel emahkan aks es petani kecil dan buruh tani atas sumber-sumber tanah. Konsep tanah dan Marj inalisasi Petani Sejak jaman raja-raja, tanah dianggap sebagai milik raja. Rakyat hanya memiliki hak garap. Hak ini dititipkan oleh raja. Sewaktu-waktu hak ini dapat ditarik kembali. Dalam wacana rakyat, tidak dikenal konsep kepemilikan tanah. Hak penguasaan dan pemilikan tanah merupakan hak para raja dan kaum bangsawan. Luasan tanah yang dikuasai ditentukan oleh jenjang jabatan politik para bangsawan dan jumlah penduduk yang dikuasainya. Petani -dalam struktur kerajaan- hanya menjadi penggarap tanah. Mereka wajib meyerahkan hasilnya kepada sikep (pengumpul upeti). Kemudian, hasil itu diserahkan kepada raja sebagai upeti. Tetapi, kedekatan petani dengan tanahnya dalam konsep ini- hanya menyangkut soal subsistensi dan keberlangsungan proses produksi, bukan soal kepemilikan1 Dalam struktur sosial demikian memang rakyat tidak memiliki hak milik tanah, sehingga penguasaan tanah tersentralisasi pada elit kerajaan. Pada jaman kolonialisme Belanda, pola hubungan kepemilikan antara raja dengan pengikutnya yang tidak jelas (irasional) dirubah oleh pemerintah kolonial menjadi hubungan sewa-menyewa yang lebih rasional. Namun posisi petani tetap tidak berubah: hanya sebagai penggarap. Bahkan nasib petani lebih buruk. Walaupun saat itu tanah dibagi-bagikan secara bebas, tetapi sebelumnya hak petani atas hasil usahataninya dicabut. Petani dimobilisasi secara besar-besaran untuk menanam tanaman perdagangan secara paksa demi kepentingan pemerintah kolonial. Sumbangan genial konsep sewa tanah ini adalah lahirnya konsep kepemilikan tanah oleh rakyat dan ganti rugi bagi tanah yang diambil alih. Keluarnya undang-undang agraria tahun 1870 (Agrarisch Wet) memunculkan pasal Domein Verklaring yang berisi “....semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom), adalah domein negara.” Dengan kebijakan ini, pemerintah kolonial berhak mengambil-alih “tanah-tanah kosong”. Tanah itu kemudian diberikan kepada para kapitalis (pemodal) Belanda untuk membuka perkebunan besar. Dalam prakteknya, karena perkebunan tersebut memerlukan tenaga kerja murah dalam jumlah besar dan produktivitas yang tinggi, tanah pertanian yang subur di daerah padat penduduk dicaplok oleh para kapitalis. Akibatnya, penguasaan tanah oleh rakyat semakin kecil. Penerapan sistem hukum ganda -yakni UU Agraria Barat (Agrarisch Wet) dan Hukum Agraria- menyebabkan petani mengalami eksploitasi ganda baik dari penjajah maupun kaum feodal adat 2. Pada masa kemerdekaan memang terjadi nasionalisasi perkebunan Belanda. Rakyat berpeluang menduduki atau merebut tanahtanah pertanian. Namun dalam perkembangannya sampai sekarang perkebunan-perkebunan tersebut tetap dikuasai oleh negara. Kemudian pada tahun 1960-an muncul pergolakan agraria yang menuntut adanya land reform agar petani dapat memiliki tanah dan menggarapnya sendiri. Namun usaha redistribusi tanah ini memunculkan chaos dan kekerasan. Terjadi pembunuhan massal 2 1 Juliantara, Dadang, dan Angger Jati Wijay a. Tanah, Rakyat dan Demokrasi di dalam Tanah, Raky at dan Demokrasi. Forum LSM/LPSM DIY, 1995. WACANA No. 10/ September - Oktober 1997 Fauzi, Noer. Transformasi Agraria dan Kesejahteraan Kaum Tani di dalam Tanah, Rakyat dan Demokrasi. Forum LSM/LPSM DIY, 1995. 1 UTAMA (massacre) terhadap ratusan ribu aktivis kaum tani kiri dalam periode 1965-19673 Pada jaman orde baru, krisis tanah semakin merebak. Pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi yang pesat di Jawa menyebabkan tekanan yang hebat terhadap tanah. Distribusi penguasaan tanah yang pincang semakin meluas sampai ke pelosok desa-desa. Pengambilalihan tanah rakyat untuk kepentingan umum seringkali menafikan hak-hak rakyat atas tanahnya. Kalaupun ada ganti rugi, jumlahnya tidak memadai. Industrialisasi yang rakus akan tanah semakin mendesak keberadaan tanah-tanah pertanian subur di Jawa. Akses rakyat atau petani terhadap tanah sangat lemah. Manfaat atas tanah selalu dinikmati oleh elit kekuasaan atau elit ekonomi baik di jaman kerajaan, kolonial maupun di jaman orde baru. Terjadi sentralisasi penguasaan tanah pada sekelompok kecil orang. Petani penggarap dan tani-buruh semakin sulit mendapatkan tanah sebagai sumber nafkah mereka. Petani gurem semakin terdesak dan terpinggirkan dalam akses penguasaan dan pemilikan atas tanahnya. Kontrol Politik atas Desa Trauma pergolakan agraria di jaman orde lama dan kelaparan yang dirasakan ketika itu menyebabkan pemerintah Orde Baru mengambil langkah-langkah antisipatif dalam rangka menangani masyarakat petani di pedesaan. Frans Husken (1989) di dalam Noer Fauzie (1995) menyebutkan dua langkah antisipatif rejim Orba menangani masyarakat tani. Pertama, kontrol politik atas daerah pedesaan. Desa harus dikontrol supaya tidak memunculkan adanya basis oposisi di desa. Kontrol politik atas masyarakat desa nampak dalam politik massa mengambang (floating mass) yang melarang partai politik bergerak di pedesaan. Langkah ini terbukti mampu memutus saluran politik antara massa dengan partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi politik kaum tani. Kedua, penyediaan bahan pangan beras dengan harga yang memadai. Harga beras harus terjangkau oleh masyarakat kota agar tidak terjadi keresahan politik, mengingat masyarakat kota (terutama buruh) sangat reaktif terhadap gejolak ekonomi. Berbagai macam lembaga dibentuk secara top down untuk menjinakkan massa petani. Fungsi parpol dan organisasi petani digantikan dengan HKTI. Lembaga ekonomi masyarakat desa diwadahtunggali melalui KUD. Struktur 3 Margo Ly on (1970) di dalam Noer Fauzi (Transformasi Agraria dan Kesejahteraan Kaum Tani, 1995). WACANA No. 10/ September - Oktober 1997 pemerintahan desa lama dirombak dan diganti dengan birokrasi baru yang sentralistik. Penetrasi kelambagaan ini mampu meredam gejolak politik di pedesaan. Sw asembada Hijau Pangan melalui Revolusi Krisis pangan pada dekade 60-an, semakin meyakinkan rejim Orde Baru untuk menerapkan program pembangunan pertanian yang menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dipilihlah strategi pembangunan pertanian melalui revolusi hijau4. Seluruh basis pertanian di pedesaan dikonsentrasikan untuk menanam padi. Petani dimobilisir untuk hanya menanam padi demi keamanan pangan. Tidak ada kebebasan bagi petani untuk menenam tanaman pangan non beras atau tanaman ekonomis lain. Strategi ini didukung dengan subsidi pertanian secara besar-besaran dalam bentuk subsidi pupuk, benih, obat-obatan, kredit murah, kebijakan harga dasar dan pembangunan irigasi. Sebagai pendukung suksesnya ketersediaan pangan, rejim Orba membentuk lembaga penyalur saprodi di tingkat desa, yaitu KUD. KUD juga berfungsi sebagai penampung hasil produksi petani. Pemerintah -melalui Departemen Pertanian- membentuk Satgas Bimas padi dan menerjunkan penyuluh pertanian ke desa-desa dalam rangka sosialisasi dan aplikasi program pertanian revolusi hijau. Petani akhirnya tidak lagi punya kemerdekaan untuk menanami tanahnya dengan tanaman budidaya yang sesuai dengan keinginannya. Industri: Tekanan Baru Tanah Pedesaan Sejak pertengahan 80-an, pemerintah mengembangkan strategi pembangunan pertanian baru, yaitu agroindustri. Strategi ini muncul sebagai solusi atas menurunnya pendapatan negara dari minyak dan gas bumi. Berbagai kebijakan dibuat untuk menyukseskan program pengembangan agroindustri, khususnya untuk memacu ekspor nasional. Akibatnya, terjadi penetrasi kapital secara besar-besaran ke desa-desa. Penetrasi ini semakin menekan petani yang sebelumnya sudah terkena dampak program revolusi hijau. Lahirlah perkebunanperkebunan besar sebagai pemasok bahan baku bagi industri pertanian (agroindustri). Karena agroindustri mensyaratkan skala usaha yang besar maka kebutuhan akan tanah juga semakin besar. Terjadilah pembukaan areal pertanian di hutan serta pengambilalihan tanahtanah produktif rakyat untuk mendukung 4 Di lapangan, revolusi hijau diterjemahkan lewat program pertanian seperti: Insus/Supra Insus dan Bimas/Inmas. 2 UTAMA agroindustri. Posisi petani terdesak karena strategi ini. kecil semakin menjadi buruh tani atau buruh di sektor industri perkotaan. Strategi ini merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU No 1/67 dan UU No 8/68. Berdasarkan kedua UU ini, pemerintah mengundang penanaman modal secara besarbesaran di pedesaan, baik modal domestik maupun asing, melalui pembukaan perkebunan besar dan industri pengolahan hasil perkebunan. Pemerintah juga memberikan hak guna usaha (HGU) dan HPH atas tanah-tanah negara. Banyak pengamat menilai, kebijakan ini tidak berbeda dengan semangat Domein Verklaring yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dahulu. Dari sisi lain, pembangunan pertanian terbukti lebih menguntungkan dan menyejahterakan petani kaya berlahan luas dan petani menengah. Sementara petani gurem dan buruh tani justru tidak dapat menikmati hasil program pertanian. Kebijakan kredit pertanian (kredit Bimas, Inmas, KUT, KIK) misalnya, hanya dapat dinikmati dan diakses oleh petani kaya berlahan luas dan petani berlahan sedang. Karena dalam memperoleh kredit tersebut harus ada agunan berupa bukti kepemilikan tanah. Jelas, petani gurem dan penggarap tidak bisa memenuhinya. Para petani gurem dan penggarap hanya bisa menikmati KCK yang besarnya tidak seberapa dan tidak memadai sebagai modal usahatani. Padahal, petani kaya yang memiliki tanah luas, bisa memiliki modal sendiri dari surplus hasil pertaniannya. Artinya, pelipatan modal hanya terjadi pada petani-petani kaya. Para petani kaya punya kesempatan mengembangkan usahanya ke non-land base agriculture maupun ke sektor industri kecil non pertanian. Sementara petani kaya semakin kaya dan memiliki banyak peluang dan akses, petani gurem dan buruh tani semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan. Selain agroindustri, industri manufaktur dan perumahan (properti) juga memberikan tekanan yang hebat dan mendorong pencaplokan tanahtanah pertanian yang produktif. Mafia pertanahan bermunculan, dan secara sistematis memaksa petani menjual tanahnya dengan ganti rugi yang sangat rendah demi kepentingan industrialisasi. Konversi lahan pertanian menjadi areal industri dan perumahan terjadi di mana-mana. Data Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1983-1993, sejumlah 0,5 juta ha lahan pertanian subur penghasil pangan di Jawa beralih fungsi menjadi areal industri, pemukiman, bisnis, pariwisata dan perkebunan swasta besar. Secara struktural kondisi ini menciptakan kepincangan antara sektor industri dan pertanian. Para petani sebagai subjek pertanian rakyat pada akhirnya termarjinalisasi. Kepemilikan tanah dan pemiskinan petani Di pedesaan sendiri telah terjadi stratifikasi sosial berdasar luasan tanah yang dimiliki. Setidaknya ada empat golongan petani di pedesaan, yaitu: petani kaya berlahan luas, petani berlahan sedang, petani berlahan sempit dan buruh tani. Sementara beberapa data menunjukkan bahwa 70% - 80% dari luasan tanah di desa dikuasi oleh (hanya) 10% - 20% penduduk. Bahkan banyak informasi terakhir menunjukkan mayoritas lahan pertanian di desa telah dikuasai oleh orang-orang luar desa. Tajamnya kesenjangan sosial ini semakin kentara dengan semakin banyaknya buruh tani dan petani gurem dalam 15 tahun terakhir. Data sensus pertanian 1993 menunjukkan jumlah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 9,53 juta rumah tangga tahun 1983 menjadi 10,94 juta rumah tangga pada tahun 1993. Dengan kata lain dalam waktu 10 tahun jumlah petani gurem naik sebesar 1,4 juta rumah tangga. Tentunya jumlah ini akan semakin besar jika buruh tani dimasukkan juga sebagai kelompok petani gurem. Fenomena ini diikuti dengan semakin banyaknya petani yang WACANA No. 10/ September - Oktober 1997 Wasana Kata Petani gurem dan buruh tani pada akhirnya mulai tersingkir karena tiadanya akses terhadap sumber-sumber tanah. Petani kecil yang masih mau bertahan, terpaksa mencari nafkah tambahan diluar kegiatan bercocok tanam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani gurem dari bercocok tanam hanya mencapai 50% dari biaya hidup minimum sebuah keluarga kecil. Jelaslah bahwa pertanian tidak dapat lagi diandalkan oleh para petani kecil ini. Dengan kata lain, telah terjadi proses pemiskinan di kalangan petani-petani gurem dan buruh tani. Para petani miskin tersebut kini bahkan tidak bisa berharap banyak bahwa proses produksi mereka akan tetap berlanjut dan menjamin tingkat subsistensi mereka. Apalagi berharap untuk dapat memiliki tanah sendiri. Rasanya, hal itu adalah sesuatu utopis. Semakin jelas bahwa tanah —yang menjadi segalanya buat petani (seperti terungkap dalam pepatah Jawa: sadhumuk bathuk senyari bumi, ditohi pecahing dhadha lan wutahing ludira)— hanyalah sebuah mitos belaka. Dalam keterpurukan petani karena ketiadaan tanah ini, pembangunan pertanian justru semakin menjerumuskan petani pada titik kesejahteraan hidup terendah. Praktek pembangunan pertanian lalu menjadi —menyitir istilah Wertheim—- : betting on the strong ...... 3