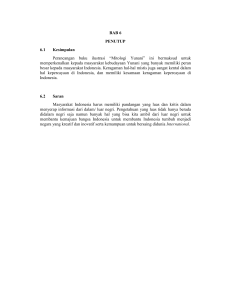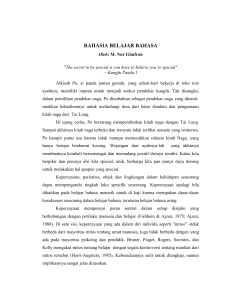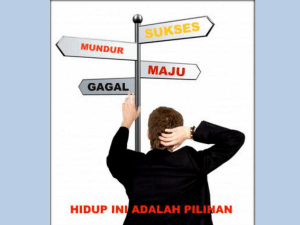DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP
advertisement

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP AGAMA MINORITAS Penyerangan dan Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan organisasi yang terdaftar dengan SK Menteri Kehakiman RI No.JA 5/23/13 tgl. 13 Maret 1953 Tambahan Berita Negara RI No.26 tgl. 31 Maret 1953. Kekerasan terhadap JAI mulai mencuat tahun 2001 saat terjadi pengrusakan terhadap rumah, mesjid bahkan pembunuhan terhadap 1 orang di Sambi Elen, NTB. Sejak itu kekerasan terhadap JAI seakan tidak ada putusnya. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengna kekerasan terbanyak antara lain di Tasikmalaya, Kuningan, Bogor, Garut, Bandung, Cimahi. Meskipun di Kalimantan, Sulawesi Selatan kekerasan juga terjadi. Di NTB warga Ahmadiyah diusir paksa beberapa kali. Pertama tahun 2001 pasca pembakaran masjid Ahmadiyah di Bayan. Pada kejadian ini 1 orang meninggal, 1 luka parah dengan bacokan dan semua warga Ahmadiyah diusir dari Bayan. Pada 2002 jemaat Ahmadiyah di Pancor, Lombok Timur, di serang. Terjadi pembakaran dan penjarahan dari rumah ke rumah. Saat itu pemerintah memberikan pilihan bahwa warga Ahmadiyah boleh tetap di Pancor asalkan keluar dari Ahmadiyah atau tetap meneguhi keyakinannya tapi meninggalkan Pancor. Pada tahun inilah warga Ahmadiyah pertama kali menghuni asrama Transito, Mataram. Tahun 2006 jemaat Ahmadiyah di Ketapang, Lingsar Lombok Barat, diserang dan diusir paksa. Hingga tahun 2013 ini, 130 orang belum dapat kembali ke kampung halamannya dan masih tinggal di transito dengan kondisi yang tidak layak. Kekerasan terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah seolah mendapatkan justifikasi dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2008, No. : KEP-033/A/JA/6/2008, No. : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat Isi SKB ini pada intinya “memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”. SKB ini sebenarnya juga “memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI”. Serta memberikan ancaman adanya sanksi untuk mereka yang melanggarnya. Tetapi dalam prakteknya, diktum mengenai JAI lebih banyak diimplementasikan. Kebijakan yang memicu SKB dan dijadikan alasan oleh pelaku kekerasan adalah fatwa MUI. Terdapat 2 fatwa, tahun 1980 dan 2005. Fatwa tahun 2005 tidak hanya menyatakan Ahmadiyah di luar Islam dan pengikutnya murtad (keluar dari Islam) tetapi juga menyatakan “Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya”. Kekerasan yang dialami JAI adalah serangan terhadap fisik, psikis, pengusiran, tidak bisa mendapat KTP, tidak bisa dicatat perkawinannya, penmbakaran rumah, pengrusakan harta lain, pembakaran mesjid, pelarangan ibadah, dan pemecatan. Sebetulnya sejak 1980 an telah ada upaya untuk menghilangkan Ahmadiyah yang berasal dari luar Indonesia. Terdapat Nota Diplomatik Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta kepada Kementerian Agama RI agar melarang kegiatan Ahmadiyah pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1984 muncul Surat Dirjen Bimas Islam No. D/BA.01/3099/84 kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi tentang larangan menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah. Pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi penyerangan oleh ratusan orang terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kp. Peundeuy Desa Umbulan, Cikeusik Pandeglang Banten. Akibatnya 3 orang Jamaah Ahmadiyah meninggal, 6 orang luka berat, serta terjadi perusakan terhadap harta benda. Peradilan berjalan tidak berimbang dan seorang korban, Deden, dihukum 6 bulan sementara 12 pelaku mendapatkan hukuman yang sangat ringan yaitu 3 sampai 6 bulan penjara. Pasca penyerangan tersebut, terjadi peningkatan laporan tentang eskalasi kekerasan, tindakan diskriminasi, ancaman, serta persekusi dari berbagai daerah. Kebijakan yang melarang JAI muncul di berbagai daerah. Catatan LBH Jakarta menunjukkan 5 Provinsi melarang Ahmadiyah dan/atau aktivitasnya yaitu Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sedangkan di level kabupaten/kota tercatat Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Kuningan,Garut Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Pandeglang, Serang, Lebak, Lombok Timur, Lombok Barat, Pekanbaru, Kampar (Riau), Samarinda, Pontianak, Konawe Selatan, Banjarmasin, Kota Bekasi Diskriminasi dan Pembatasan terhadap Para Penganut Penghayat Kepercayaan Stigma dan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan/kebatinan dapat kita telusuri dari UU 1/PNPS/1965. Bagian penjelasan poin 2 menyatakan. Namun hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaranajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada. Sulit diketahui latar belakang peristiwa di tahun-tahun tersebut sehingga muncul pandangan seperti ini. Salah satu tulisan menyebut “pasca tragedi 1965, aliran kepercayaan/kebatinan sering dikaitkan dengan tragedi 1965.” Aliran kebatinan yang awal-awal dinyatakan sesat adalah Aliran kebatinan perjalanan dengan Surat Keputusan no.SK-23/PAKEM/1967 23 Mei 1967.Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka Pakem mengeluarkan surat keputusan No.02/Kep/PAKEM/1970 tentang pelarangan/pembubaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Demikian pula di Kabupaten Sumedang Kejari dengan alasan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kabupaten Sumedang merupakan penjelmaan dari partai yang dilarang oleh Pemerintah, serta pengikutnya berasal dari pemeluk agama Islam yang telah keluar dari Islam. Lebih jauh Kejari Kabupaten Sumedang mengatakan Aliran Kebatinan Perjalanan jelas-jelas di dalam melakukan ibadahnya telah menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Pelarangan dan pembubaran organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan juga dilakukan oleh Pakem di Kabupaten Subang. TAP MPR No.II/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, dan pembinaannya tidak mengarah kepada agama baru. Implikasinya aliran kepercayaan/kebatinan tidak berada di bawah Departemen Agama. Pada awalnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dibentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah pimpinan Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No.40/1978. Kemudian pemerintah mengeluarkan Kepres No.21/2003 yang menempatkan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah pimpinan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. Kejagung juga mengeluarkan surat keputusan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat. Adapun latar belakang pembentukan Tim Pakem tersebut menurut konsideran SK Kejagung itu adalah untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan : Agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru; Dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ; Pelaksanaan aliran kepercayaan benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Pengaturan ini menunjukkan kecurigaan yang besar dari pemerintah terhadap aliran kepercayaan. Sebenarnya ajaran yang digolongkan ke dalam aliran kepercayaan terdiri dari 2 jenis yaitu : Agama yang menempel pada kelompok adat tertentu Agama yang bersumber dari agama zaman dahulu di Indonesia dan berkembang menjadi aliran-aliran tertentu Pada periode 1971 s/d 1983, Kejagung telah melakukan pelarangan terhadap Aliran Kepercayaan Manunggal dan Ajaran Agama Jawa Sanyoto. Konghucu Diskriminasi dan Pembatasan terhadap Penganut Kong Hu Cu Kong Hu Cu sebenarnya disebut dalam PNPS 1/PNPS/1965 yang menjadi UU melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peenyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNP/1965 menyatakan “...agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.”“Karena 6 macam agama ini adalah Agamaagama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini”. Mesipun demikian, Kong Hu Cu dilarang pada masa Orde Baru pasca Inpres 14/1967 yang berlaku saat ditetapkan pada tanggal 6 Desember 1967. Inpres tersebut pada intinya berisi : 1. Pelaksanaan tata cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. 2. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan di depan umum, hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. 3. Penentuan lingkup agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat). 4. Inpres ini juga memandatkan pengamanan dan penertiban terkait kebijakan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung. Sebelum Inpres ini, telah muncul Instruksi Kabinet Presidium pada tahun 1966 no. 127/U/KEP/1966 tentang Kebijakan Penggantian Nama untuk WNI yang memiliki nama Tionghoa. Pada tahun yang sama terbit Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang isinya “untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan”. Selain itu muncul pula Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan dan menyebarkan semua jenis barang cetakan dalam bahasa dan aksara Tionghoa Tidak hanya itu saja, gerak-gerik masyarakat Cinapun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) Keseluruhan aturan dan kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa tersudut dan tidak leluasa menjalankan kegiatan keagamaan/keyakinan tradisi mereka seperti Kong Hu Cu. Larangan penggunaan aksara Cina juga berarti menghambat penyebaran buku-buku keagamaan/keyakinan yang berisi aksara Cina. Selain itu, ekses larangan ini adalah mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan perkawinan. Mereka juga mendapat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya umat Kong Hu Cu yang berpindah agama. Diperkirakan, akibat sikap diskriminasi pemerintahan Orde Baru, saat ini umat Kong Hu Cu hanya berjumlah 2 juta orang. Ekses pelarangan agama Kong Hu Cu terlihat dalam kasus penolakan Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat perkawinan Kong Hu Cu antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan di rumah Ibadah Boen Bio dengan alasan agama atau aliran kepercayaan Kong Hu Cu tidak tercatat dalam macam-macam agama yang diakui di Indonesia. Penolakan pencatatan dilakukan dengan surat tanggal 15 Desember 1995 nomor 474.201/294/402.803/95 pada tanggal 23 Juli 1996 berdasarkan pada ketentuan yang didasari pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1995 Nomor 4683 Tahun 1995. 1. 2. 3. 4. 5. Ternyata terdapat beberapa dasar bagi Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan penolakan tersebut yaitu surat-surat atau instruksi yang melarang Kantor Catatan Sipil mencatat atau mendaftar perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan dan Kong Hu Cu, yaitu Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/650/1979. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor R-489/D.1/6/1983. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2535/PUOD/90 tanggal 25 Juli 1990. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.2/309/PUOD/95 tanggal 19 Oktober 1995. Surat DPR Republik Indonesia Nomor PW 006/3249/DPR RI/1996 tanggal 12 Juli 1996. Kemudian mereka mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Gugatan ini ditolak melalui Putusan tanggal 3 September Nomor 14/G/TUN/1996/PTUN.SBY. Mereka kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun juga ditolak melalui putusan tanggal 17 Maret 1997 Nomor 05/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY. Baru melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/TUN/1997 tentang Perkawinan Kong Hu Cu antara Budi Wijaya alias Po Bing Bo dan Lany Guito alias Gwie Ay Lan, gugatan mereka dipenuhi. Kantor Catatan Sipil Surabaya harus melakukan pencatatan perkawinan dalam register perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keputusan Presiden No.6/Tahun 2000 pemerintah mencabut Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967. Selain itu, Keppres ini juga memerintahkan semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut Keppres 6/2000 menyatakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Pada masa pemerintahan Megawati Keppres Nomor 19/2002 menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional. Ekses dari larangan Kong Hu Cu pada masa Orba masih dirasakan saat ini. Pada masa itu klenteng Kong Hu Cu bernaung di bawah majelis tridarma, bagian dari majelis agama Buddha. Pengurus dan umat Kwan Sing Bio berdemo ke Kemenag meminta Matakin atau majelis Konghucu keluar dari kelenteng itu. Sebab selama ini kelenteng di Tuban (Jawa Timur) ikut majelis tridarma. Tridarma dianggap sudah mencakup Konghucu sehingga tidak perlu ada Matakin. Koleksi Pusat Dokumentasi HAM ElSAM Sumber Artikel KKPK