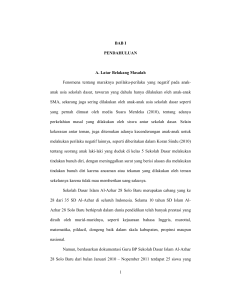studi islam di barat dan di timur tengah: pengamatan
advertisement

1 Bahan untuk Ceramah ‘Experiencing Islam in America’ @america November 19, 2015 STUDI ISLAM DI BARAT/AMERIKA SERIKAT DAN DI TIMUR TENGAH: Pengamatan dan Pengalaman Selintas Azyumardi Azra, CBE Studi Islam di Barat, khususnya di Amerika Serikat, tidak ragu lagi, merupakan bidang kajian tersendiri yang cukup kompleks. Adalah na’if menganggap studi Islam di Barat/AS sebagai seragam; terdapat berbagai corak dan kecenderungan dalam studi-studi Islam di Barat—khususnya di AS yang perlu kita cermati. Tetapi, terlepas dari keragamannya, studi Islam di Barat, sulit dipungkiri, turut membentuk cara pandang sarjana-sarjana Muslim-termasuk yang berasal dari Indonesia-tamatan universitas-universitas Barat terhadap Islam. Studi Islam di Eropa dan AS merupakan bagian integral dari arus intelektual lebih luas di Barat; bahkan pada masa awal menjadi bagian tak terlepaskan dari arus politik di Barat—yang selanjutnya memunculkan apa yang disebut ‘orientalisme’. Sebagai bagian dari arus intelektual itu, setiap pembicaraan dan kajian tentang Islam di Barat jelas banyak dipengaruhi perkembangan intelektualisme ‘saintifik’ sebagai hasil dari perkembangan dunia keilmuan secara keseluruhan. Kajian Historis Secara garis besar terdapat dua bentuk pendekatan dalam kajian Islam: teologis dan sejarah agama-agama. Pendekatan kajian teologis, yang bersumber dari tradisi dalam kajian tentang Kristen di Eropa, menyodorkan pemahaman normatif mengenai agama-agama. Karena 2 itu kajian-kajian diukur dari kesesuaiannya dengan dan manfaatnya bagi keimanan. Tetapi dengan terjadinya marjinalisasi agama dalam masyarakat Eropa, kajian teologis normatif semakin cenderung ditinggalkan para pengkaji agama-agama. Sedangkan pendekatan sejarah agama-agama berangkat dari pemahaman tentang fenomena historis dan empiris, sebagai manifestasi dan pengalaman masyarakat-masyarakat agama. Penggambaran dan analisis dalam kajian bentuk kedua ini tidak atau kurang mempertimbangkan klaim keimanan dan kebenaran sebagaimana dihayati para pemeluk agama itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan keilmuan di Barat yang sejak abad 19 semakin fenomenologis dan positivis, pendekatan sejarah agama menjadi paradigma dominan dalam kajian agama, termasuk Islam, di Barat. Sebelum kita merinci lebih jauh tentang kedua bentuk pendekatan ini ada baiknya dikemukakan lebih dulu, bahwa sarjana dan pengkaji Islam di Barat berakar pada beberapa disiplin tradisional. Pertama, adalah mereka yang berakar pada disiplin humaniora tradisional, mencakup filologi, filsafat, literatur dan sejarah. Kedua, yang berakar pada disiplin-disiplin teologis dan teologi, seperti sejarah kitab suci dan sejarah institusi agama. Ketiga, yang berakar pada ilmuilmu sosial, khususnya antropologi, linguistik dan psikologi. Keempat, yang berakar pada studi kawasan-ini sebenarnya merupakan salah satu titik tolak Orientalisme, yakni Dunia Timur-khususnya kajian Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Terlepas dari tingkat penggunaannya, kedua bentuk pendekatan yang tadi merupakan tradisi sentral kajian Islam yang terus dipegangi sepanjang setengah abad terakhir. Dalam pendekatan pertama tadi, eksplorasi dilakukan atas apa yang disampaikan kepada Muslim atau Nabi Muhammad yang kemudian diartikulasikan menjadi sistemsistem teologi, hukum dan ibadah. Eksplorasi ini dilakukan terutama dengan menggunakan metode-metode yang dikembangkan para filolog, yakni metode pengkajian teks secara seksama. Berdampingan dengan itu, terdapat peningkatan minat mengkaji Islam sebagai sistem praktek keagamaan yang hidup dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Minat ini terlihat jelas dalam kajian pionir yang dilakukan sarjana semacam Goldziher, Massignon atau Snouck Hurgronje, yang selanjutnya dikembangkankan para sarjana yang terlatih dalam disiplin humaniora, seperti sejarah; dan ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi dan politik. 3 Pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis ketimbang “kumpulan tatanan doktrin”, yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, menemukan momentumnya kuat dalam pertumbuhan kajian Islam di beberapa universitas besar dan terkemuka di Amerika Serikat. Tradisi ini tentu saja pertama kali bertumbuh di Eropa, yang selanjutnya dikembangkan lebih komprehemsif di AS oleh sarjana semacam D. B. Macdonald (1863-1943) dan H. A. R. Gibb. Macdonald mengajar di Hartford Seminary, Connecticut, AS, sejak 1893. sedangkan Gibb mengajar di Oxford sampai 1955 sebelum menjadi guru besar di Harvard. Macdonald dan Gibb terutama tertarik kepada kehidupan historis masyarakat-masyarakat Muslim. Ini terlihat dari buku Macdonald, The Religious Attitude and Life in Early Islam (1909), atau karya Gibb, Modern Trends in Islam (1949). Keduanya memperingatkan bahaya mengkaji hanya Islam normatif, seperti dirumuskan para ‘ulama, dengan mengabaikan Islam yang hidup di tengah masyarakat umum. Gagasan ini mendapatkan lahan subur dalam diri para ahli kajian Islam di sejumlah universitas AS yang memperoleh pendidikan sebagai sejarawan dan ilmuwan sosial. Sejak 1950-an sejumlah universitas di AS mulai mengembangkan pusatpusat studi kawasan (area studies) Islam, yang pada dasarnya mencakup berbagai disiplin berbeda tetapi memperoleh pendidikan khusus dalam bahasa, kebudayaan dan masyarakat Muslim di wilayah tertentu. Dengan penekanan pada kajian historis, tidak heran kalau di AS dan Barat umumnya bertumbuh minat kuat pada apa yang disebut sebagai ‘popular Islam’, khususnya tareka-tarekat sufi. Seperti diketahui, sejak masa Goldziher, tarekat sufi telah diakui sebagai saluran tempat mengalirnya arus spiritualitas Islam. Terdapat berbagai cara mempelajari fenomena tarekat sufi. Tentu saja terdapat kajian tradisional yang menggunakan pendekatan teologi dengan mengkaji teks di mana diungkapkan tentang cara atau metode untuk dekat kepada dan mencapai pengalaman langsung dengan Tuhan. Tetapi pada pihak lain, kian banyak kajian antropologis yang menjelaskan fenomena tarekat dari segi kepercayaan dan praktek yang berkembang di sekitar tasawuf terorganisasi ini; kultus terhadap para wali, ziarah ke tempat suci, kepercayaan pada validitas washilah (intercession), dan seterusnya. 4 Kajian-kajian semacam ini dapat dikatakan merupakan upaya untuk keluar dari jebakan konseptual yang muncul sebagai akibat pembedaan yang tajam antara ‘Islam yang sebenarnya’ (true Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab suci atau dirumuskan ‘ulama dengan ‘Islam yang tidak murni’ (impure Islam), ‘Islam peripheral’ dan semacamnya. Dalam perspektif ini, apapun yang dipercayai rakyat sebagai Islam adalah Islam; dan apa yang disebut sebagai ‘popular Islam’ memiliki signifikansi khas, meski para ahli syari’ah dan mutakallimun mungkin akan mengutuknya sebagai ‘Islam yang tidak benar’. Tetapi, dari wawasan ini mncullah perluasan penting dalam kajian tentang Islam di Barat. ‘Popular Islam’ tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ‘bid’ah sesat’ atau ‘keimanan dan praktek menyimpang’ dari ‘Islam yang sebenarnya’. Tetapi merupakan ekspresi historis yang absah dari Islam. Hasil-hasil yang disodorkan kajian antropologis dan historis seperti ini, bagaimanapun pada gilirannya mendorong munculnya pertanyaan: sekali kita melangkah keluar definisi normatif yang diberikan ahli fiqh dan mutakallimun tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘masyarakat Islam’? Apakah ‘Islam’ itu ‘satu’ atau justru terdapat banyak ‘Islam’; dan jika terdapat banyak ‘Islam’, apakah ini abadi? Batas-batas apakah yang membuat suatu masyarakat dapat disebut ‘Islami’? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dicoba jawab khususnya oleh sejumlah antropolog Amerika khususnya. Clifford Geertz, misalnya, dalam Islam Observed (1972)menggunakan bahan dari Jawa dan Maroko untuk menjawab pertanyaan: dalam pengertian apakah masyarakat-masyarakat di Indonesia dan Marokko dapat disebut ‘Ialami’? Apakah kesamaan dasar yang membuat keduanya ‘Islami’. Dalam menjawab pertanyaan ini, sayangnya, Geertz terlalu menekankan Islam kultural sehingga mengabaikan Islam doktrinal yang sedikit banyak membentuk ‘teks’ Islam kultural tersebut. Michael Gilsenan, antropolog yang banyak mengkaji fenomena sufi di Timur Tengah, berpendapat bahwa Islam jika dilihat dari konteks sosial bukanlah obyek tunggal. Kata ‘Islam’ dapat mengacu kepada konsep-konsep, simbol-simbol dan ritual tertentu yang turut membentuk kesadaran bersama (collective consciousness) berbagai masyarakat yang menganut Islam. Tetapi Islam itu sendiri tak urung pula dibentuk mereka. Tegasnya, menurut Gilsenan, Islam adalah sebuah kata yang mengidentifikasikan berbagai hubungan praktek, 5 representasi, simbol, konsep dan pandangan dunia di dalam masyarakat tertentu dalam hubungan tersebut, dan mereka berubahsecara signifikan sepanjang waktu. Dalam kajian-kajian Barat tentang Islam memang masih menjadi masalah, bahwa sekalipun kata ‘Islam’ didefinisikan dengan sangat hati-hati, tetap dapat dipersoalkan apakah ia dapat digunakan sebagai kategori untuk menjelaskan sejarah masyarakat-masyarakat yang kebanyakan penduduknya adalah Muslim. Terdapat keengganan di kalangan banyak ahli-Barat atau Timur-untuk menggunakan kategori ‘Islam’ dan sebaliknya menggunakan kategori ‘Muslim’. Karena itulah kita menemukan judul karya ‘sejarah masyarakat [atau ummat] Muslim’ ketimbang ‘sejarah Islam’, atau ‘Dunia Muslim’ ketimbang ‘Dunia Islam’. Dengan demikian, secara implisit diakui adanya distansi antara Islam dengan realitas empiris, sosiologis dan historis masyarakat-masyarakat penganut Islam. Terlepas dari masalah senang atau tidak, ini sekaligus mengisyaratkan terdapatnya semacam problem dalam kategori ‘Islam’ itu sendiri. Karena itulah di beberapa negara Barat, khususnya AS dan Prancis, sejarawan dan ilmuan sosial membawa kategori-kategori mereka sendiri, yang bersumber dari budaya sosiologis dan kultural pada mereka sendiri, yang bersumber dari budaya sosiologis dan cultural di masa mereka. Di antara yang paling banyak digunakan pula dalam kajian Islam adalah kategori Marxis atau post-Marxis, atau kategori-kategori yang dikembangkan sejarawan yang berasosiasi dengan jurnal Prancis, Annales. Dalam konteks ini, sejarawan Prancis, Fernand Braudel, dalam Le Méditerranée et le monde méditerranéen a l’epoque de Philippe II (1949) mencoba menjelaskan sifat perkembangan seluruh dunia yang terbentang di sekitar Laut Tengah, dan dengan demikian konsep yang sekaligus lebih luas dan lebih sempit dari pada ‘Dunia Muslim’. Jadi, kategori ‘Islam’ cukup jarang masuk ke dalam kajiankajian tentang Islam di AS atau Barat umumnya. Ini secara mencolok terlihat dalam suatu studi seminal tentang sejarah Timur Tengah yang ditulis di masa kontemporer oleh Andre Raymond berjudul Artisans et commercant au Caire au 18eme siècle (1999). Faktor-faktor pokok penjelasan yang diberikan Raymond adalah sistem administrasi dan fiskal Turki Utsmani dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. ‘Islam’ masuk ke dalam anaisis hanyalah sebagai faktor 6 subsider, yakni sejauh hukum Islam mempengaruhi harta waris dan distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim Kairo. Contoh menarik lainnya adalah berkenaan dengan dilakukannya kolokium internasional pada tahun 1965 untuk mempertimbangkan gagasan tentang ‘kota Islam’, yang diasumsikan mempunyai karakteristik tersendiri baik dalam formasi fisik maupun struktur sosialnya yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam. Kesimpulan yang dihasilkan kolokium adalah konsep ‘Islamic city’ kurang bermanfaat sebagai kategori penjelasan dari pada, misalnya, kategorikategori ‘kota abad pertengahan’ atau ‘kota praindustri’ atau bahkan ‘kota Timur Dekat’ atau ‘kota Afrika Utara’. Pengabaian kategori Islam seperti ini dalam kajian Islam di AS atau Barat umumnya, sebagaimana bisa diduga, tentu saja menimbulkan kegusaran baik di kalangan ahli Barat sendiri dan, apalagi, di kalangan banyak sarjana Muslim. Dalam kaitan ini, argumen kuat yang paling sering dikemukakan adalah: orang tidak dapat mengabaikan bahwa Islam memang menjadi kategori dan faktor dalam perkembangan masyarakat-masyarakat yang memeluk agama ini. Tegasnya, dalam masa awal kebangkitan dan pertumbuhan Islam, orang tak bisa menolak kenyataan agama baru ini menyebar di berbagai wilayah untuk kemudian membentuk dan mengembangkan sistem sosial budaya atau peradaban umumnya, yang unik dan khas. Usaha paling ambisius untuk menggunakan Islam sebagai kategori yang dilengkapi penjelasan-penjelasan historis lainnya untuk memahami Islam dan Dunia Muslim dilakukan M. G. S. Hodgson, gurubesar University of Chicago, dalam karya besarnya sebanyak 3 jilid, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Society (1974). Lebih dari itu, seperti tersirat dalam anak judul karya ini, Hodgson juga berusaha menempatkan Islam dalam konteks sejarah universal. Ini menunjukkan kepedulian pengarang terhadap hubungan antara individualitas dan kolektivitas, dan juga kesadarannya tentang tempat ‘Dunia Islam’ [perhatikan penggunaan istilah ini secara eksplisit] dalam kesatuan sejarah lebih luas. Dengan demikian, ia juga melihat sejarah Islam sebagai kerangka temporal lebih luas-sebagai kontinuitas tradisi kultural lebih tua di wilayah ‘Bulan Sabit Subur’ (Fertile Crescent), Iran, dan Mesir, menjangkau kebudayaan Babylonia dan Mesir Kuno, yang sekarang diekspresikan dalam bahasa Arab dan dalam respons intelektual dan artistik terhadap kitab suci baru (al-Qur’an). 7 Kajian Islam yang dilakukan di AS dan Barat umumnya, jelas tengah mengalami perubahan. Penelitian dan kajian yang dilakukan di tengah kehadiran subyek yang mereka teliti dan kaji. Semakin banyak ahli Barat yang menyadari kehadiran Islam dan Dunia Muslim yang hidup dan berubah; tidak sekedar catatan masa silam. Peningkatan apresiasi terhadap Islam di kalangan sarjana Barat inilah yag kemudian memunculkan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Orientalisme Baru (new Orientalism). Kebangkitan Orientalisme Baru membuka peluang lebih besar bagi terciptanya interaksi dan pertukaran keilmuan lebih dinamis dan positif di antara sarjana-sarjana Barat non-Muslim dengan sarjanasarjana Muslim. Bahkan riset dan pemikiran terus dilakukan secara bersama dalam suasana dialogis. Masyarakat internasional studi Islam sekarang lebih dari komunitas terbuka. Dalam kongres Orientasi Internasional yang diselenggarakan pada 1928 di Oxford, terdapat tidak lebih selusin sarjana Muslim dari 750 peserta; dan sarjana Muslim ini memainkan peran sangat kecil dalam proceedings. Sekarang, konperensi-konperensi Asosiasi Kajian Timur Tengah di Amerika Utara, melibatkan sejumlah besar sarjana Muslim; dan sebagian mereka menjadi anggota paling aktif dan menonjol. Perkembangan seperti ini memunculkan pergeseran keseimbangan dalam beberapa disiplin kajian Islam di antara sarjanasarjana Muslim dengan non-Muslim. Tak sedikit sarjana Muslim yang begitu menonjol sehingga mempengaruhi seluruh sarjana lain dalam kajian yang mereka lakukan. Salah satu contoh adalah Halil Inalcik, yang karya tentang sejarah Dinasti Utsmani membentuk paradigma dan mempengaruhi pandangan seluruh spesialis dalam sejarah ‘Utsmani. Atau Fazlur Rahman, gurubesar asal Pakistan yang mengajar di University of Chicago, yang karyanya menjadi rujukan penting bagi sarjana baik di Barat maupun di negara-negara Muslim. Meski terjadi perkembangan positif seperti itu, harus diakui, kritik terhadap studi Islam di AS dan Barat umumnya tetap bergema. Terdapat sedikitnya dua kritik yang dikemukakan secara cukup keras baik dari kalangan sarjana Muslim maupun non-Muslim. Kritik pertama datang dari sarjana Muslim taat, yang percaya, misalnya l-Qur’an dalam pengertian literal adalah kata-kata Tuhan yang diwahyukan-Nya melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Adalah mustahil bagi sarjana Muslim taat untuk menerima analisis ilmiah apapun yang akan dan dapat mengurangi al- 8 Qur’an menjadi sekedar hasil pemikiran Muhammad. Secara tradisional terdapat kecenderungan di kalangan sarjana Barat nonMuslim mengabaikan keimanan Muslimin ini. Padahal seharusnya, meski para sarjana Barat non-Muslim tidak menerima keimanan tersebut, setidaknya mereka dapat menghormatinya. Karena sikap kaum Muslim terhadap al-Qur’an mengekspresikan keimanan yang mereka pegangi, yang membentuk kepribadian mereka secara individual maupun kolektif. Di sini Fazlur Rahman dapat dikutip sebagai representasi ekspresi sarjana Muslim tentang al-Qur’an. Menurutnya, adalah esensial memelihara al-Qur’an sebagai dasar keimanan, pemahaman dan tingkah laku moral. Tetapi, menurut dia, al-Qur’an juga harus dilihat sebagai buku bimbingan bagi seluruh umat manusia (huda li alnas). Para ahli hukum (fuqaha) keliru karena mengambil pernyataanpernyataan tertentu dari al-Qur’an secara terpisah, dan mengangkat dari ayat-ayat tersebut –melalui analogi/qiyas yang ketat –hukumhukum dan ketentuan yang berlaku sepanjang masa. Menurut Rahman, perlu memandang al-Qur’an secara kritis sebagai kesatuan dalam kacamata keilmuan moderen, dengan memahami maksud utamanya dan mengambil daripadanya ajaran-ajaran yang cocok untuk keadaan dalam waktu dan tempat tertentu. Kritisisme terhadap alQur’an ini perlu pula diterapkan dalam melihat Hadits. Kritik lainnya terhadap studi Islam di Barat datang dari sarjana umumnya, tidak hanya dari mereka yang berpegang pada keimanan Islam. Kritik inilah yang sering disebut sebagai kritik terhadap apa yang disebut ‘Orientalisme’. Terdapat tiga kritik dalam hal ini. Pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis yakni menjelaskan seluruh fenomena masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan Muslim dalam kerangka konsep tunggal dan tidak berubah. Dengan kata lain, kajian Islam di Barat cenderung menggeneralisasi fenomena yang berlaku pada masyarakat Muslim. Dalam contoh lebih jelas, terdapatnya radikalisme kelompok-kelompok Muslim tertentu di Timur Tengah, misalnya, dipandang sebagai berlaku dan absah juga dalam masyarakat-masyarakat Muslim di tempat-tempat lain. Kedua, kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi kepentingan-kepentingan politis. Inilah kritik paling populer hingga saat ini. Dalam konteks ini, menurut argumen para pengkritik, kajiankajian tentang Islam dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat 9 terhadap masyarakat-masyarakat Muslim, antara lain, dengan menciptakan citra tidak benar dan distortif tentang Islam dan masyarakat Muslim. Ketakutan Eropa tentang revolusi Islam pada abad-abad silam, misalnya, belakangan ini dihidupkan kembali melalui apa yang disebut sebagai ‘clash of civilizations’ Ketiga, kajian-kajian tentang Islam di Barat senderung merupakan upaya melestarikan kebenaran-kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis, yang padahal tidak atau hampir tidak mempunyai dengan kenyataan yang hidup. Sarjana barat, dalam usaha mereka memahami Islam dan masyarakat Muslim membawa kategori-kategori penjelasan yang belum tentu mampu dan cocok untuk menjelaskan subjek kajian mereka tersebut secara akurat. Sarjana-sarjan Barat, misalnya, mengunakan kategori-kategori Marxis untuk menjelaskan perkembangan sejarah tertentu di kalangan kaum Muslim, seraya menolak dan mengabaikan kategori-kategori Islam sendiri. Hasilnya adalah distorsi pemahaman terhadap perkembangan historis dan sosiologis masyarakat-masyarakat Muslim. Di sini ada baiknya sekali lagi kita mengutip pengakuan Fazlur Rahman. Ia mengatakan, terlepas dari berbagai kelemahan kajiankajian tentang Islam dari wawasan yang dikembangkan sementara sarjana Barat, sama seperti ia juga banyak belajar dan memperoleh wawasan dasar tentang Islam dari banyak guru Muslimnya. Lebih jauh, menurut Rahman, memang adalah tugas sarjana Muslim menegakkan Islam. Tetapi ini tidaklah harus menghalangi terciptanya kerjasama antara sarjana Muslim dengan non-Muslim, khususnya pada tingkat pemahaman intelektual. Pemahaman intelektual dan apresiasi terhadap Islam cukup mungkin muncul dari sarjan Barat non-Muslim yang tidak berprasangka, sensitif dan berpengetahuan luas. Pendekatan Normatif Dengan corak dan karakteristik studi Islam di AS atau Barat umumnya, seperti dikemukakan di atas, jelaslah salah satu akar utama cara pandang sarjana Muslim Indonesia yang memperoleh pendidikan lanjutan tentang Islam di universitas-universitas Barat. Pendekatan yang lebih historis terhadap Islam turut membentuk cara pandang mereka yang sering disebut lebih ‘liberal’ menyangkut Islam. ‘Liberalisme’ pandangan itu berkaitan dengan concern mereka umumnya lebih pada kenyataan historis dan sosiologis Islam 10 ketimbang doktrin Islam itu sendiri. Di sini mereka kemudian sering dituduh sebagai tidak atau kurang mempunyai kesetiaan kepada Islam, dan sebaliknya menjadi pengikut Orientalis belaka. Padahal, masalahnya terletak bukan pada soal setia atau tidak kepada Islam melainkan pada pendekatan semata-mata. Sebaliknya, dalam persepektif perbandingan, sarjana-sarjana Indonesia tamatan Timur Tengah sendiri dipandang secara seragam sebagai lebih besar setia dan mempunyai komitmen lebih tinggi terhadap Islam. Ini mengesankan, pendidikan dan lingkungan berpikir mereka di Timur Tengah adalah seragam pula; yakni normatif dan tidak liberal. Benarkah kesan ini ? Harus diakui, meski pendidikan tinggi di Timur Tengah sangat mengesankan pendekatan pendekatan normatif dan ideologis terhadap Islam, lingkungan berpikir mahasiswa tidak seragam sebagaimana dibayangkan banyak orang. Memang arus pendekatan normatif terhadap Islam sangat kuat di kalangan akademis perguruan tinggi si Timur Tengah. Tetapi ini bukan gambaran selengkapnya, karena cukup pula arus yang menekankan pendekatan historis dan sosiologis yang dipandang liberal tadi. Bahkan, tidak kurang terdapat contohcontoh liberalisme pemikiran di lingkungan universitas dan dunia umumnya. Pemikiran liberal seperti ditampilkan Hanaf, atau Zaki Najib Mahmud atau Abdellahi Ahmed an-Na’im, gurubesar Emory University, AS, dalam masa akhir, merupakan diskursus absah dari pendekatan dan pemikiran tentang Islam di Timur Tengah. Liberalisme pandangan terhadap Islam di Timur Tengah bahkan dapat dikatakan jauh lebih maju daripada liberalisme para sarjana Muslim Indonesia tamatan Barat. Harus segera diakui, sejauh ini belum ada sarjana kita yang berfikir seliberal Hanafi atau al-Naim. Lebih jauh lagi, jika Amerika atau Barat disebut sebagai akar liberalisme pemikiran sarjana kita, maka dunia perguruan tinggi dan mayarakat imiah Timur Tengah, kecuali di Arab Saudi, jauh lebih awal berinteraksi dengan dunia studi Islam di Barat dengan pendekatannya yang khas tadi terhadap Islam. Jika STAIN/IAIN/UIN mengirimkan sejumlah dosen mudanya belajar ke Barat baru beberapa dasawarsa terakhiri, sebaliknya Al-Azhar sudah menyelenggarakan program pengiriman tenaga dosen untuk belajar ke Barat secara teratur sejak tahun 1931. Yang mereka pelajari ternyata bukan hanya ilmuilmu sosial dan humaniora yang dapat dikaitkan dengan Islam, tetapi bahkan ilmu-ilmu Islam itu sendiri; untuk menyebut beberapa contoh 11 saja; dalam missi al-Azhar 1935, Afifi’ Abd al-Fahham mendapat gelar PhD dalam tasawwuf dari Sorbonne; Muhammad al-Fahham mendapat gelar PhD dalam bidang nahwu juga dari Sorbonne; dan Ibrahim jamal al-Din memeperoleh gelar PhD dalam ilmu akhlak dari Universitas Montpellier, Prancis. Jika liberalisme pemikiran terhadap Islam juga merupakan salah satu arus dalam dunia akademis dan diskursus intelektual di Timur Tengah, kenapa Justru sarjana-sarjana Indonesia tamatan Timur Tengah terkesan lebih bersikap normatif? Dalam kaitan ini menarik untuk mengutip disini hasil penelitian Mona Abaza tentang mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, Khususnya di al-Azhar. Menurut Abaza, mahasiswa Indonesia d Timur tengah sebelum tahun 1970-an, berbarengan dengan meningkatnya apa yang disebut sebagai fundamentalisme agama, arus pemikiran lebih normatif terhadap Islam juga mengalami momentum. Tetapi tidak berarti pemikiran dan pendekatan liberal terhadap Islam punah sama sekali. Di sini persoalannya menjadi lebih kompleks. Abaza secara meyakinkan menunjukan semakin dominannya nada fundamentalis normatif di kalangan mahasiswa Indonesia di al-Azhar berkaitan tidak hanya dengan pergeseran orientasi arus pemikiran di Timur Tengah, tetapi juga berhubungan erat dengan realitas kehidupan sehari-sehari mahasiswa Indonesia itu sendiri. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi menyangkut amat kecilnya jumlah dana beasiswa, rumitnya birokrasi universitas, sistem akademis yang tidak memungkinkan menyelesaikan kuliah dalam waktu cepat, merupakan masalahmasalah yang turut membentuk sikap dan cara berpikir mahasiswa Indonesia di al-Azhar. Persoalan internal mahasiswa seperti ini mempersempit kiprah berinteraksi dan terlibat dalam arus pemikiran yang berkembang lebih luas di balik dinding-dinding kampus. Mona Abaza boleh jadi sedikit berlebihan ketika menyatakan, rasa frustasi yang muncul dari berbagai masalah yang mereka hadapi, dengan cepat memberi lahan subur bagi banyak mahasiswa Indonesia di al-Azhar dalam masa belakangan ini untuk memeluk lebih erat nada fundamentalisme. Karena itu, literatur karya para pemimpin al-Ikhwan al-Muslimun, seperti al-Banna dan Sayyid Quthb menjadi bacaan populer. Sedangkan mereka yang membaca karya pemikir yang dipandang liberal, seperti Fazlur rahman, merupakan kelompok minoritas belaka. Suasana intelektual inilah yang kelak dibawa banyak alumni Timur Tengah ke tanahair . 12 Corak kajian Islam, baik dengan pendekatan Barat—khususnya AS--maupun Timur Tengah, adalah bagian absah dari diskursus intelektualisme Islam di Dunia Muslim. Kedua corak ini seharusnya tidak dipertentangkan-karena itu hanya counter-productive-melainkan harus dipandang sebagai komplementer satu sama lain. Bahkan kedua pendekatan ini sebaliknya dipadukan atau diharmoniskan sedemikian rupa untuk mendenamiskan pemikiran Islam di tanahair. *AZYUMARDI AZRA, CBE, lahir 4 Maret 1955 di Lubuk Alung Sumatera Barat, adalah gurubesar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah; dan pernah menjabat Direktur Sekolah PascaSarjana UIN Jakarta sejak Januari 2007 sampai April 2015. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN,1998-2002, dan UIN, 2002-2006). Memperoleh gelar MA (Kajian Timur Tengah), MPhil dan PhD (Sejarah/Comparative History of Muslim Societies) dari Columbia University, New York (1992) with distinction. Pada Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam humane letters dari Carroll College, Montana, USA. Ia juga gurubesar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9); Selain itu juga anggota Dewan Penyantun International Islamic University, Islamabad, Pakistan (2005-12); Komite Akademis The Institute for Muslim Society and Culture (IMSC), International Aga Khan University (London, 2005-2010). Dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset, dia adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2005-sekarang); anggota Dewan Riset Nasional (DRN, 2005-9). Dia juga anggota Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP, Tokyo, 1999-2001); Asian Research Foundation-Asian Muslim Action Network (ARF-AMAN, Bangkok, 2004-sekarang); The Habibie Center Scholarship (2005-sekarang); Ford Foundation International Fellowship Program (IFP-IIEF, 2006-12); Asian Scholarship Foundation (ASF, Bangkok, 2006-10); Asian Public Intellectual (API), the Nippon Foundation (Tokyo, 20072014); anggota Selection Committee Senior Fellow Program AMINEF-Fulbright (2008); dan Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA, 2010-12). Selain itu, dia anggota Dewan Pendiri Kemitraan—Partnership for Governance Reform in Indonesia (2004-sekarang); Dewan Penasehat United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York, 2006-8); International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm (2007-13); Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-14); Institute of Global Ethics and Religion, USA (2004-sekarang); LibforAll, USA (2006-sekarang); Center for the Study of Contemporary Islam (CSCI, University of Melbourne, 2005-7); Tripartite Forum for Inter-Faith Cooperation (New York, 2006-sekarang); anggota World Economic Forum’s Global Agenda Council on the West-Islam Dialogue (Davos 2008-sekarang). 13 Dia juga adalah pemimpin redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies (Jakarta, 1994-sekarang); Journal of Qur’anic Studies (SOAS, University of London, 2006-sekarang); Journal of Usuluddin (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006-sekarang); Jurnal Sejarah (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005-sekarang); The Australian Journal of Asian Law (Sydney, Australia, 2008-sekarang); IAIS Journal of Civilisation Studies (International Institute of Advanced Studies, Kuala Lumpur, 2008-sekarang); Journal of Royal Asiatic Society (JRAS, London, 2009-sekarang); Journal Islamic Studies (Islamic Research Institute, Islamabad, 2010-sekarang; Jurnal Akademika (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010-sekarang); dan Journal of Islamic Studies (Oxford Centre for Islamic Studies, 2013-16). Dia telah menerbitkan lebih dari 36 buku, termasuk Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context (Jakarta & Singapore, TAF, ICIP, Equinox-Solstice, 2006); Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development (Mizan International: 2007); (co-contributing editor), Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (London: Ashgate: 2008); Varieties of Religious Authority: ¨Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam (Singapore: ISEAS, 2010); contributing-editor, Indonesia dalam Arus Sejarah: Jilid III, Kedatangan dan Peradaban Islam, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2012; dan contributing editor, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jilid III, 2015; Lebih 30 artikel dan bab buku berbahasa Inggris telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal pada tingkat internasional. Pada 2005 ia mendapatkan The Asia Foundation Award dalam rangka 50 tahun The Asia Foundation atas peran pentingnya dalam modernisasi pendidikan Islam; dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI, pada 15 Agustus 2005 mendapat anugerah Bintang Mahaputra Utama RI atas kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat; pada September 2010, ia mendapat penghargaan gelar CBE (Commander of the Most Excellent Order of British Empire) dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Inggris atas jasa-jasanya dalam hubungan antar-agama dan peradaban. Kemudian pada 28 Agustus 2014 ia mendapat penghargaan ‘MIPI Award’ dari Masyarakat Imu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Selanjutnya, pada 4 Agustus 2014, ia dianugerahi ‘Commendations’ dari Kementerian Luarnegeri Jepang atas jasanya memperkuat saling pengertian antara Jepang dan Indonesia; dan 18 September 2014 dia terpilih sebagai salah satu dari tiga penerima anugerah bergengsi Fukuoka Prize 2014 Jepang atas jasa dan kontribusi signifikannya pada peningkatan pemahaman masyarakat internasional terhadap budaya Asia. Pada 25 Juni 2015 dia mendapat penghargaan ‘Cendekiawan Berdedikasi’ dari Harian Kompas; pada 20 Agustus 2015 dia terpilih menyampaikan ‘LIPI Sarwono Memorial Lecture’ dalam rangka ulang tahun ke-48 LIPI; dan pada 21 Agustus 2015 dia terpilih menerima ‘Penghargaan Achmad Bakrie’ dalam Pemikiran Sosial. Selain itu, pada 2009 dia terpilih sebagai salah satu di antara ‘The 500 Most Influential Muslim Leaders’ dalam bidang Scholarly (kesarjanaan/keilmuan) oleh Prince Waleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, 14 Georgetown University, Washington DC dan The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania di bawah pimpinan Prof John Esposito dan Prof Ibrahim Kalin. Dia dapat dikontak melalui [email protected] / [email protected]
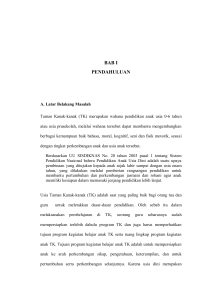
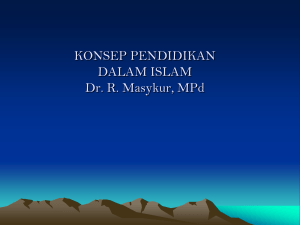

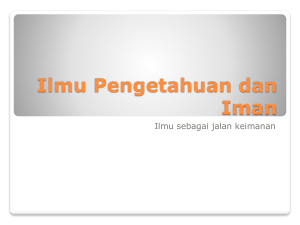
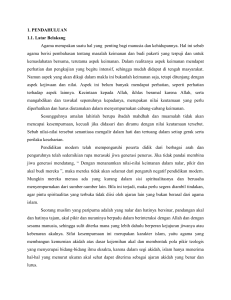
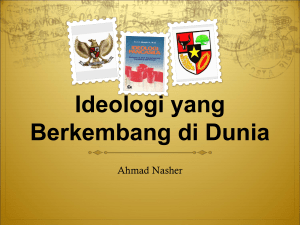
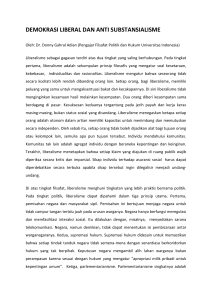
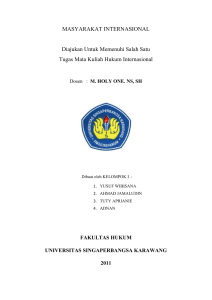

![Modul Pendidikan Agama Khatolik [TM1]](http://s1.studylibid.com/store/data/000101410_1-b4cb9e47485eadc2a3d44a7db8cdca17-300x300.png)