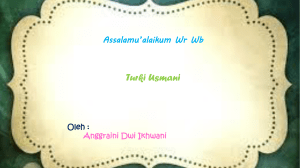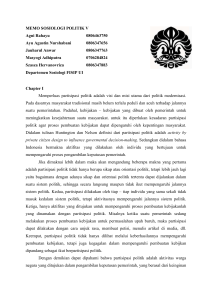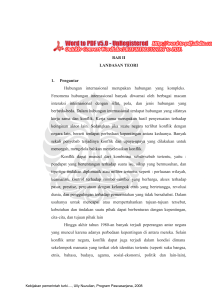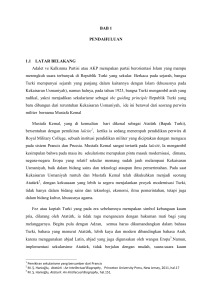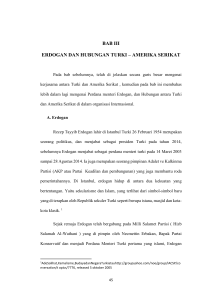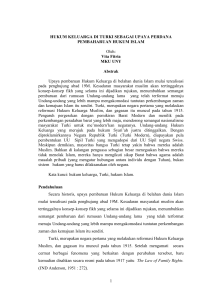etika dalam kitab suci dan relevansinya
advertisement

ETIKA DALAM KITAB SUCI DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN STUDI KASUS DI TURKI Oleh Komaruddin Hidayat Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang difahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos. [1] Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan manjadi dua: obyektivisme dan subyektivisme. Yang pertama berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat obyektif, terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang disebut faham rasionalisme dalam etika. Suatu tindakan disebut baik, kata faham ini, bukan karena kita senang melakukannya, atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. Tokoh utama pendukung aliran ini ialah Immanuel Kant, sedangkan dalam Islam --pada batas tertentu-ialah aliran Muitazilah. [2] Aliran kedua ialah subyektifisme, berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subyek tertentu. Subyek disini bisa saja berupa subyektifisme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subyek Tuhan. Faham subyektifisme etika ini terbagi kedalam beberapa aliran, sejak dari etika hedonismenya Thomas Hobbes sampai ke faham tradisionalismenya Asy’ariyah. Menurut faham Asy’ariyah, nilai kebaikan suatu tindakan bukannya terletak pada obyektivitas nilainya, melainkan pada ketaatannya pada kehendak Tuhan. Asy’ariyah berpandangan bahwa menusia itu bagaikan ‘anak kecil’ yang harus senantiasa dibimbing oleh wahyu karena tanpa wahyu manusia tidak mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita sepakati bahwa etika ialah suatu kajian kritis rasional mengenai yang baik dan yang buruk, bagaimana halnya dengan teori etika dalam kitab suci? sedangkan telah disebutkan di muka, kita menemukan dua faham, yaitu faham rasionalisme yang diwakili oleh Mu’tazilah dan faham tradisionalisme yang diwakili oleh Asy’ariyah. Munculnya perbedaan itu memang sulit diingkari baik karena pengaruh Filsafat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayat-ayat al-Qur’an sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. Di dalam al-Qur’an pesan etis selalu saja terselubungi oleh isyaratisyarat yang menuntut penafsiran dan perenungan oleh manusia. [3] ETIKA DAN KEBEBASAN Menurut aliran voluntarisme rasional, suatu tindakan etis akan terwujud bilamana tindakan itu produk pilihan sadar dalam situasi bebas, bukannya terpaksa. Suatu pertanggungjawaban etis bisa diberlakukan hanya ketika seseorang berbuat dalam keadaan sadar dan bebas. Dengan demikian, etika senantiasa mengamsumsikan kebebasan. Semakin besar wilayah kebebasan, semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya. Dalam perspektif di atas, maka faham Jabariah yang berpandangan bahwa tindakan manusia adalah bagaikan,gerak wayang, yang ditentukan oleh ‘dalang’ tak ada tempat bagi konsep etika voluntarisme rasional Kantianisme. Etika voluntarisme rasional melahirkan suatu pandangan terhadap manusia sebagai sosok manusia berakal yang dewasa suatu pandangan positif bahwa manusia memang pantas mendapatkan julukan ahsan-u ‘l-taq wim, puncak ciptaan Tuhan meskipun keunggulan kualitas manusia itu masih harus diperjuangkan dan disempurnakan sendiri oleh manusia. Barangkali saja dalam perspektif yang demikian ini kita bisa memahami mengapa pewahyuan Tuhan melalui para rasulNya telah diakhiri, sementara kehidupan menusia kian hari kian berkembang sedemikian kompleknya. Sebelum kerasulan Muhammad problema kehidupan manusia tidak sekomplek pascaMuhammad, namun justeru pada masa-masa itu Allah sering mengirimkan rasulrasulNya. Mengapa demikian, biasanya kita mengajukan dua jawaban. Pertama, tuntutan Allah yang diturunkan kepada manusia. Kedua, manusia dengan kemampuan rasionalitasnya telah mampu mengevaluasi kehidupan kesejarahan untuk menciptakan kebaikan hidup mereka. Klaim yang menyatakan Islam sebagai agama universal dan agama paripurna tersirat pada surat al-Maidah ayat 3 dan surat alAnbiya ayat 107. Yang pertama menyebutkan bahwa Islam adalah nikmat Tuhan yang telah disempurnakan, yang kedua menyatakan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Secara dogmatis theologis kedua klaim di atas memang sudah lazim diterima oleh umat Islam, namun secara rasional dan empiris tampaknya masih perlu dirumuskan serta diuji kembali kebenarannya dalam perjalanan sejarahnya. Dari analisis bahasa dan sosio-historis, Islam hadir bukannya dalam ruang kosong, melainkan dalam wacana yang memiliki sifat lokal dan partikular. Secara eksplisit disebutkan bahwa al-Qur’an disebarluaskan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa mau tidak mau bersifat budaya, ia terikat dengan kaidah-kaidah sosial dan konsensus budaya. Jadi, universalitas pesan al-Qur’an akan bisa terkomunikasikan kalau manusia juga memiliki dimensi universal. Dalam hal ini rasionalitas dan substansi bahasalah yang secara jelas merupakan dimensi universal yang melekat pada manusia. Manusia dibedakan dari binatang terutama adalah karena manusia merupakan animal symbolicum, yaitu makluk yang hidup dengan symbol-symbol. [4] Berbahasa pada dasarnya adalah berpikir, dan berpikir tidaklah mungkin tanpa bahasa, meskipun berbahasa tidak selalu harus berbicara ataupun menulis. Karena adanya rasionalitas dan kemampuan berbahasa maka suatu masyarakat tercipta, komunikasi antar mereka berlangsung, dan dunia di sekitarnya memperoleh makna. Barangkali fenomena inilah yang telah diisyaratkan oleh al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 31 dimana Allah telah mengajar ‘nama-nama’ pada Adam. Karena rasionalitas dan sistem symbol yang dimiliki manusia maka realitas masa lampau bisa direkontruksi, diceritakan dan dihadirkan kembali di hadapan kita melalui narasi sejarah. Suatu nilai, cita-cita dan gagasan masa lampau pun bisa diwariskan kepada generasi ke generasi lantaran adanya sistem simbol ini. Dan sesungguhnya hanyalah al-Qur’an yang secara eksplisit dan tegas agar umat Islam mengembangkan rasionalitas dan sistem simbol untuk membangun peradabannya. Kita bisa membuat suatu pengandaian, kalau saja al-Qur’an bertentangan dengan rasionalitas, maka bisa dipastikan bahwa Islam telah terdistorsi dalam perjalan sejarahnya. Lebih dari itu etika Islam akan teranomali dalam kehidupan modern. Dengan kata lain, al-Qur’an dan pesan-pesannya kini telah menjadi bagian integral dari realitas sejarah masa lampau dan tetap hidup sampai kini, tanpa adanya revisi dan campur tangan Tuhan, baik isi maupun redaksionalnya. Di sini tersirat pandangan positif al-Qur’an tentang manusia. Kalau kita telaah ayat-ayat al-Qur’an segera kelihatan bahwa etika al-Qur’an amat humanistik dan rasionalistik. Pesan al-Qur’an seperti halnya ajakan kepada keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, dan lain sebagainya, semuanya amat sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia sebagaimana tertuang dalam karya-karya para filosof. Etika Islam memiliki antisipasi jauh ke depan dengan dua ciri utama. Pertama, etika Islam tidak menentang fithrah manusia. Kedua, etika Islam amat rasionalistik. Sekedar sebagai perbandingan baiklah akan saya kutipkan pendapat Alex Inkeles mengenai sikap-sikap modern. Setelah melakukan kajian terhadap berbagai teori dan definisi mengenai modernisasi, Inkeles membuat rangkuman mengenai sikap-sikap modern sabagai berikut, yaitu: kegandrungan menerima gagasan-gagasan baru dan mencoba metodemetode baru; kesediaan buat menyatakan pendapat; kepekaan pada waktu dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lampau; rasa ketepatan waktu yang lebih baik; keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi; kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung; menghargai kekuatan ilmu dan teknologi; dan keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan. [5] Rasanya tidak perlu lagi dikemukakan di sini bahwa apa yang dikemukakan Inkeles dan diklaim sebagai sikap modern itu memang sejalan dengan etika al-Qur’an. Dalam diskusi tentang hubungan antara etika dan moral, problem yang seringkali muncul ialah bagaimana melihat peristiwa moral yang bersifat partikular dan individual dalam perspektif teori etika yang bersifat rasional dan universal. Islam yang mempunyai klaim universal ketika dihayati dan direalisasikan cenderung menjadi peristiwa partikular dan individual. Pendeknya, tindakan moral adalah tindakan konkrit yang bersifat pribadi dan subyektif. Tindakan moral ini akan menjadi pelik ketika dalam waktu dan subyek yang sama terjadi konflik nilai. Misalnya saja, nilai solidaritas kadangkala berbenturan dengan nilai keadilan dan kejujuran. Di sinilah letaknya kebebasan, kesadaran moral serta rasionalitas menjadi amat penting. Yakni bagaimana mempertanggungjawabkan suatu tindakan subyektif dalam kerangka nilai-nilai etika obyektif, tindakan mikro dalam kerangka etika makro, tindakan lahiriah dalam acuan sikap batin. Dalam teori etika, tindakan moral mengamsumsikan adanya otonomi perbuatan manusia. Menurut Islam, untuk mencapai otonomi dan kebebasan sejati tidaklah harus ditempuh dengan menyatakan ‘kematian Tuhan’ sebagaimana diproklamasikan oleh Nietzsche atau Sartre misalnya, keduanya berpendapat bahwa manusia akan terkungkung dalam kekerdilan dan ketidakberdayaan serta dalam perbudakan selama tindakan moralnya masih membutuhkan kekuatan dan kesaksian dari Tuhan. Oleh karenanya, menusia haruslah bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, bukannya pada Tuhan. Lebih dari itu, untuk mencapai derajat kemanusiaannya secara prima manusia harus meniadakan Tuhan dan kemudian menggali dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya. Dasar pemikiran seperti di atas tentu saja berangkat dari konsepsi ketuhanan dalam tradisi Kristen. Dalam sejarah pemikiran Barat kita mencatat bahwa untuk mencapai derajat filsuf biasanya mereka mesti bentrok dengan doktrin gereja tentang Tuhan. Sedangkan dalam Islam justru ketika tindakan kita diorientasikan pada Tuhan Yang Maha Absolut, Yang Maha Bebas, maka kita tidak akan terjebak dalam relativisme dunia dan sebaliknya kita akan terangkat menuju pada atmosphere Yang Maha Otonom. Pengakuan bahwa kita bukan makluk sempurna yang sudah jadi, dan kemudian diikuti dengan usaha kontinyu menuju Yang Maha Sempurna, di sanalah terletak makna keimanan yang dinamis. Menurut Kant, puncak rasionalitas pada akhirnya akan mengantarkan pada pintu keimanan yang bersifat supra-rasional. Tuhan, keimanan, dan kemerdekaan bukanlah obyek ilmu pengetahuan. Semua berada di luar jangkauan rasio, namun puncak rasionalitas mengantarkan menusia untuk melakukan loncatan ke arah sana. [6] ETIKA ISLAM: PENGAMATAN DI TURKI Islam di Turki mempunyai sejarah panjang, bisa ditelusuri ke belakang sejak abad ke-19 sampai hari ini. Bangsa Turki yang sekarang berpusat di wilayah Balkan dan Anatolia itu pada mulanya pendatang dari daerah Turkestan, terletak antara Rusia dan Cina. Untuk menyederhanakan diskusi kita, saya akan membagi periodisasi Islam di Turki, yaitu Islam di masa Ottoman dan Islam semasa Republik, yang berlangsung sejak 1924 hingga hari ini. Ada tiga pertanyaan pokok yang hendak diangkat dalam uraian berikut ini. Pertama, bagaimanakah pergumulan antara nilainilai keislaman dan tradisi bangsa Turki di masa Ottoman? Kedua apakah dampak gerakan Kemal Ataturk terhadap kelanjutan Islam di Turki? Ketiga, bagaimana perkembangan Islam di Turki dewasa ini dalam etika Islam? ISLAM DI MASA OTTOMAN Dinasti Ottoman yang berdiri pada abad ke 14 dan berakhir pada awal abad-20 tentu saja merupakan lahan kajian sejarah yang amat kaya sehingga tidak mungkin makalah singkat ini bisa manyajikan potret global yang memadai. Namun begitu bisa saja kita membuat karakterisasi keislaman bangsa Turki pada masa Ottoman, meskipun bahaya simplifikasi dan reduksi tidak bisa dielakkan. Secara antropologis bangsa Turki kadangkala disebut ‘war nation’ ataupun ‘war machine.’ Hal ini terlihat dari karir mereka dalam perluasan wilayah kekuasaan Ottoman yang terbentang sejak dari Afrika, India, Persia dan bahkan sampai Eropa. Sejak mulanya ideologi Ottomanisme dan Islamisme saling kait berkait sedemikian rupa, keduanya didukung oleh ethos dan keunggulan militer yang sulit dicari tandingnya. Baik semasa Abasid maupun Seljuk bangsa Turki ini telah dikenal sebagai pasukan berkuda yang handal. Militansi kemiliteran ini ditopang oleh spirit jihad melawan orang kafir Eropa sehingga dengan begitu semangat penaklukan semakin berkobar. Abad-16 merupakan masa puncak kejayaannya, yang diikuti kemudian oleh berbagai krisis, dan berakhirlah dinasti ini setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I. Krisis ini datang dari dua jurusan dari dalam dan dari luar. Massa rakyat di bawah kekuasaan Ottoman adalah kaum petani yang tidak mendapat pendidikan secara baik. Dengan mengandalkan kontrol secara militer dan doktrin ketaatan pada Sultan sebagai pemimpin agama, pada mulanya rakyat secara mudah bisa dikuasai. Tetapi situasi demikian tidak bertahan selamanya. Berbagai kelompok agama, suku, dan bangsa yang bernaung di bawahnya lama kelamaan berkembang sebagai ancaman, terutama setelah meletusnya Revolusi Perancis dimana semangat nasionalisme menggulir dan menggerogoti kekuasaan Ottoman. Sejak itu secara diam-diam muncul tiga ideologi, yaitu Ottomanisme, Islamisme, dan Turkisme. Karena kekuasaan cenderung berpihak pada ambisi pribadi bukannya akal sehat, Rajaraja Osmani (Ottoman) tetap mempertahankan ideologi Ottomanisme, sementara Islam cenderung diperalat sebagai ideologi pendukungnya. Dengan kata lain, keislaman semasa Ottoman adalah keislaman yang berciri ideologi untuk ambisi kekuasaan, bukannya keislaman yang melahirkan ethos keilmuan dan peradaban modern. Krisis Ottoman semakin terlihat di permukaan ketika apa yang disebut ‘millet system’ semakin otonom dari kontrol pusat sementara Eropa sudah bangkit dari keterbelakangannya. [7] Millet system dan capitulation adalah suatu bentuk perjanjian antara Ottoman dan kekuasaan asing untuk menjalin kerjasama ekonomi berdasarkan pengelompokan agama. Sebagai akibatnya kelompok-kelompok agama nonMuslim yang berada di bawah kekuasaan Ottoman lamalama berubah manjadi perpanjangan tangan dari kekuatan Kristen Eropa untuk menghancurkan Ottoman dari dalam, melalui jalur penguasaan ekonomi oleh kelompok minoritas non-muslim. [8] Krisis yang melanda Libanon hari ini akar penyebabuya bisa ditelusuri pada millet system ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Don Peretz, "The general decay of Ottoman governmental institutions coincided with the rise of more powerful European nation states”. [9] Berbagai cara untuk mengantisipasi kemerosotan Ottoman telah dicoba, misalnya saja oleh gerakan Tanzimat, Turki Muda, dan Sultan Mahmud II (1808). Di antara ciriciri gerakan yang ditawarkan ialah berusaha untuk mengenalkan mesin percetakan, ilmu kemiliteran, dan semacamnya yang dipandang sebagai gerakan baru di Eropa. Namun berbagai usaha itu gagal, antara lain disebabkan oleh fanastisme teologis yang menimbulkan keyakinan kuat di kalangan Sultan bahwa Tuhan mesti berpihak pada dirinya, dan orang kafir Eropa tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan Islam. Lebih dari itu, sistem pembagian kekuasaan secara rasional dengan melibatkan partisipasi massa sama sekali di luar jangkauan para sultan. Pendeknya Sultan adalah pusat kekuasaan, sedangkan gagasan-gagasan baru yang dikenalkan dari Eropa yang tengah bangkit itu dicurigai sebagai kekuatan yang merongrong wibawa Sultan serta dicap sebagai budaya kafir Eropa. Demikianlah, Islam yang pada mulanya telah mengantarkan kejayaan Ottoman, pada akhirnya Islam di ideologisasikan sebagai kekuatan penyangga Ottoman yang nampak besar tetapi sangat rapuh. Tampaknya perjumpaan antara Islam dan bangsa Turki Usmani lebih menonjol dalam melahirkan ethos jihad dan ketaatan pada uli al-amri ketimbang ethos kerja dan ethos keilmuan. Oleh karenanya kita akan kecewa kalau mencari tokoh-tokoh pemikir Islam yang brilian yang dilahirkan oleh bangsa Turki Usmani. GERAKAN KEMAL ATATURK: MASALAH PENAFSIRAN Mengawali uraian saya mengenai Islam pasca-Ottoman saya akan mengutip tiga pendapat sarjana ahli tentang Turki: After a century of Westernization, Turkey has undergone immense changes-greater than any outside observe had thought possible. But the deepest Islamic roots of Turkish life and culture are still alive, and the ultimate identity of Turk and Muslim in Turkey is still unchallenged. (Bernard Lewis, 1961) It has often been thought that this secularism signified the separation of state and religion somewhat along the lines of French laicism and the involved and anti-religious policy seeking to eliminate Islamic faith. These assumptions are no correct. In fact, the new Turkish Republican regime tried to implement its constitutional mandate of freedom of concience by setting up goverment agencies charged with helping citizens to approach Islam through reason rather than tradition. (Howard A. Reed, 1981) The revitalization of Islam in this country is partly due to the success of the campaign to universalize education which was the foundation stone of the secular Turkish Republic and partly to economic achievements in the period 1950-1980. Syerif Mardin, 1989) Pada 29 Oktober 1923 secara resmi Republik Turki diproklamirkan oleh sidang parlemen dimana Mustafa Kemal terpilih sebagai Presiden pada umurnya yang ke-42 tahun. Gerakan republiken ini sekaligus menghadapi dua musuh, yaitu kekuatan Sekutu yang hendak menguasai Turki, dan kekuatan tradisional yang berpihak pada ideologi teokratik Osmani. Bila kita telaah bunyi ke-6 sila ideologi Kemalisme, akan terlihat begitu jelas bahwa setiap silanya merupakan kritik dan sekaligus anti-thesis terhadap paradigma Ottomanisme. [10] Sila yang dianggap kontroversial tentu saja dengan dinyatakannya bahwa Turki menganut faham sekuler. Pernyataan ini dinilai oleh dunia Islam lainnya sebagai tindakan ‘murtad’ dalam pemikiran politik Islam. Tetapi kalau gerakan Ataturk kita tempatkan dalam perspektif sejarah, akan terlihat bahwa gerakannya merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan gerakan sebelumnya. Apa yang dilakukan Ataturk merupakan pengejawantahan ide-ide gerakan modernisasi dan westernisasi yang pernah dicanangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, terutama Ziya Gokalp. Zia Gokalp, starting with Durkheim, formulated his own concept of community and society, which he defined as culture group and cilivization group. Turkism, according to Gokalp, aimed at synthesis of Turkish nationalism, islam, and modernization, althouh its formula was very different from that of the Islamic modernist.” [11] Apa yang dirumuskan Gokalp di atas sampai kini hampir tidak pernah ditentang oleh para intelektual Turki. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara cultural dan intelektual Islam tetap bertahan dan bahkan sebagai identitas bangsa Turki sampai hari ini. Bila semasa Ottoman Islam telah mengalami ideologisasi untuk mendukung ambisi kekuasaan, kini keislaman bangsa Turki lebih bersifat individual dan cultural. Dengan ungkapan lain, Ataturk, sebagaimana Gokalp, akan sependapat untuk mengatakan “Islam-Yes, Negara Islam-No”. Yang secara tegas-tegas ditentang oleh gerakan Ataturk adalah Ideologi Klerikisme, bukannya nilai-nilai Islam. Bahkan dalam prateknya sikap Ataturk begitu ekstrim mengikis warisan klerikisme Ottoman, hal ini tidak bisa diingkari. Namun begitu, adakah cukup sah untuk menghukum Ataturk sebagai pengkianat dan telah membuat ‘blunder’ bagi perkembangan Islam di Turki ataukah justeru Ia telah tampil sebagai penyelamat eksistensi Islam bagi bangsa Turki, kita dihadapkan pada masalah interpretasi sejarah. Ketika Turki Usmani berada di ambang kehancuran, terutama setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I, Ataturk melihat bahwa satu-satunya ideologi gerakan yang bisa memobilisasi massa dan kaum intelektual Turki waktu itu tak ada lain kecuali ideologi nasionalisme. Sedangkan model pembaharuan dan alternatif satusatunya ialah meniru Barat. Ideologi kekhalifahan tidak lagi memiliki daya panggil untuk berjihad melawan kekuatan Sekutu. Bahkan sejak sebelum meletusnya Perang Dunia ke-I beberapa wilayah Ottoman telah menunjukkan usahanya untuk memberontak dan melepaskan diri dari pusat simbol nasionalisme. Di sini sosok ‘nasionalisme’ menampilkan dua fungsinya yang berlawanan. Ketika Ottoman pada puncak kejayaan, Eropa menggunakan isu nasionalisme untuk memobilisasi massa melawan Eropa. Demikianlah, sebagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia, ideologi nasionalisme dan Islamisme secara simbolik digunakan Ottoman. Kemudian, bagaimana kita mesti merumuskan peran Ataturk dan gerakan revolusinya dalam perspektif perjalanan Islam di Turki? Ada kemiripan antara Ottoman dan gerakan Ataturk melihat Islam. Yaitu Islam didekati secara amat pragmatik untuk tujuan politik. Sebagai pengagum Durkheim, Ataturk melihat Islam sebagai refleksi sosial masyarakat Turki yang telah berakar sedemikian rupa yang memiliki kekuatan integratif bagi pertumbuhan bangsa Turki. Dengan demikian, sejak semula tokoh-tokoh gerakan modernisasi dan westernisasi di Turki tidak pernah menyatakan anti-agama, melainkan ingin mengadakan rasionalisasi agama, agar agama menjadi kekuatan penopang bagi kemajuan bangsa Turki. Jadi, kalaupun Ataturk bisa dianggap penyelamat bagi kelangsungan Islam di Turki dari ancaman Eropa dan dari penetrasi para missionaris Kristen, jasanya terhadap Islam merupakan implikasi tidak langsung dari dedikasinya dalam membela bangsa Turki dengan semangat nasionalismenya. Sebagaimana dikemukakan oleh Syerif Mardin, sistem pendidikan Barat yang dipaksakan oleh Ataturk ternyata telah berjasa besar bagi peningkatan intelektual 'kaum santri.' Sistem pendidikan Barat yang sejak awal abed-19 hendak diterapkan di Turki oleh kalangan intelektual muda dan selalu ditentang oleh jajaran Sultan, baru berhasil direalisir pada awal abad-20 dengan cara paksa dan setelah Ottoman berada diujung kehancuran. Dengan demikian, kalau saja Revolusi Ataturk ini berlangsung seabad sebelumnya, mungkin sekali nasib dunia Islam tidak akan tertinggal sedemikian jauhnya dari Barat dalam bidang iptek dan sosial kemasyarakatan. Bagaimana ketertutupan Ottoman dari pengaruh gerakan modernisme Eropa waktu itu diungkapkan oleh Bernad Lewis sebagai berikut: ... the scientific awakening, humanism, liberalism, rationalism, the enlightenment - all great European adventures and confilcts of ideas passed unnoticed and unreflected in society to which they were profoundly alien and irrelevant. The same is true of the great social, economic, and political changes. The rise and fall of the baronage, the rise of the new middle class, the struggle of money and land, of city-state, and Empire all the swift yet complex evolution of European life and society, have no parallel in the Islamic and Middle Eastern civilization of the Ottomans. [12] EKSPERIMEN SEJARAH YANG MONUMENTAL Suatu hal yang sudah pasti amat berharga bagi dunia Islam pada umumnya ialah bahwa Turki telah melakukan eksperimen sejarah, secara terang-terangan menyatakan sebagai negara sekuler serta mengambil Barat sebagai model modernisasinya. Tidak lama setelah meletusnya Revolusi Iran (1979), beberapa wartawan asing berdatangan ke Turki dengan perhitungan bahwa negara yang akan mudah tersulut oleh Revolusi itu ialah Turki. Dugaan itu tidaklah terlalu salah. Pertama, pemeluk Syiah di sana diperkirakan sekitar 10 juta, meskipun angka ini tidak pernah terungkap secara resmi. Kedua, walaupun Turki dinyatakan sebagai negara sekuler, Islam tetap berakar kuat pada masyarakat Turki, sementara agama selain Islam tak ada hak hukum untuk menyebar-luaskan missinya. Republik Turki yang berjumlah sekitar 55 juta itu sebanyak 99% adalah muslim dan antara ‘keislaman' dan 'keturkian' telah menyatu sebagai identitas diri setiap orang Turki, betapapun kadar dan corak keislaman mereka. Sebutan 'sekuler' bagi negara Turki sejak mulanya sesungguhnya tidak tepat kalau istilah sekuler itu difahami dalam konteks negara Barat. Di Barat paham sekularisme muncul antara lain sebagai akibat logis dari doktrin gereja dan akibat pertumbuhan sains, teknologi dan ekonomi, dimana etika Kristiani secara epistemologis tidak sanggup menghubungkan antara faham modernisme dan keyakinan agama. Sedangkan di Turki, sebagaimana dikemukakan Syerif Mardin, hasil westernisasi dan modernisasi sistem pendidikan yang diimport Ataturk justeru pada gilirannya telah memberikannya peluang dan fasilitas bagi umat Islam Turki untuk beradaptasi dengan dunia Barat tanpa harus terserabut keyakinan agamanya. Jadi, corak keislaman yang muncul dewasa ini bisa dikatakan sebagai keislaman pascaOttoman dan pasca-Kemalisme. Terutama sejak 1O tahun terakhir ini, secara ideologis antara Kemalisme dan Pancasila hanya berbeda dalam teorinya saja, namun pada praktek kenegaraan tidak jauh berbeda, yaitu baik Turki maupun Indonesia bukanlah negara teokratis, bukan pula sekuler. Negara bertanggungjawab bagi pembinaan dan pengembangan Islam bagi masyarakat Turki. Hal ini antara lain termanifestasikan dalam pembinaan sekolah-sekolah agama, sejak dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, sejak dari pengangkatan para imam atau khatib sebagai pegawai negeri sampai pengangkatan Atase Agama pada kedutaan Turki untuk memberikan pelayanan agama pada masyarakat Turki di negeri orang. Secara sosiologi, barangkali saja keislaman model Turki akan juga dilalui oleh masyarakat Islam lainnya ketika mereka memasuki kehidupan modern. Salah satu cirinya ialah agama cenderung sebagai urusan pribadi, sebagai tuntutan etis terjadinya depolotisasi dan deideologisasi agama, praktek ibadah yang cenderung “longgar" meningkatnya minat orang pada tasawuf. Semua ini begitu menyolok menggejala di Turki atau bahkan telah menjadi corak keberagamaan mereka. Satu hal yang mereka tidak miliki, dibanding Indonesia, ialah rasa ‘persaingan’ dengan agama lain di dalam negeri sendiri. Lebih dari itu, baru akhirakhir ini saja mulai muncul generasi baru yang merepresentasikan generasi Islam pascaOttoman dan pasca-Kemalis, yaitu generasi yang tetap konsisten dan memiliki wawasan keislaman dan sekaligus juga wawasan sikap kemodernan sebagaimana yang dilihat Gokalp ataupun Ataturk pada masyarakat Barat. PENUTUP Dari eksperimen sejarah yang dilakukan Turki, hasilnya memperkuat teori yang mengatakan bahwa konsep sekularisme Barat tidak akan tumbuh ketika ditabur atau diterapkan dalam masyarakat muslim. Kedua, semakin modern dan semakin rasional seseorang atau masyarakat, keislaman mereka cenderung terefleksikan dalam etika pribadi dan sosial, sedangkan hubungannya dengan Tuhan cenderung pada pendekatan sufistik. Ketiga, meskipun pada level praksis dan ideologi Islam senantiasa dipengaruhi oleh tradisi lokal serta kepentingan-kepentingan subyektif, secara epistemologis Islam tetap memiliki vitalitas yang bersifat rasional, sehingga dengan demikian modernisasi tidak akan menjadikan ancaman bagi Islam. -------------------------------------------CATATAN 1. Taylor, Paul W., Problems of Moral Philosophy. California: Deckenson Publishing Compant Inc., p. 3 2. Hourani, George F., Reason and Traditon in Islamic Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, p. 25 3. Ayat al-Qur’an berulangkali menuntut pembacanya agar berjihad dengan menggunakan akalnya untuk menangkap pesan-pesan etis yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya adalah hal yang logis saja bahwa dalam sejarah Islam selalu terjadi perbedaan dan konflik intelektual yang dinamis antara sesama ahli pikir. 4. Lihat Erns Cassirer, An Essay on Man, Yale University Press, 5. Weiner, Myron., Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan, Gajah Mada University Press, 1980, p. xii 6. Lihat karya-karya Immanuel Kant, terutama Critique Pure Reason dan Religion within the Limit of Reason Alone. 7. Peretz, Don, The Middle East Today, New York, 1986, p. 59 8. Ibid, loc. cit. 9. Ibid, p. fi2 10. Ke-6 sila dalam ideologi Kemalisme ialah: republikanisme, nasionalisme, populisame, sekularisme, etistisme, revolusionisme. semua sila di atas secara konotatif merupakan kritik frontal terhadap ideologi Ottomanisme. 11. Lihat Ergun Ozbodun (ed)., Ataturk, Founder of Modern State, London, 1981. Juga dalam Modern Turkey: Continuity and Change, Opladen, 1984 12. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, 1967, p. 482