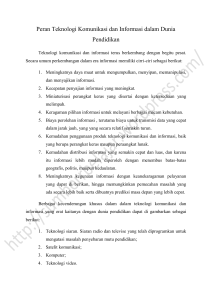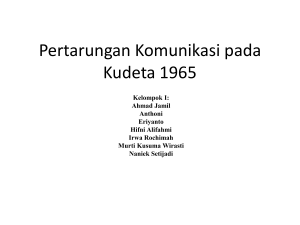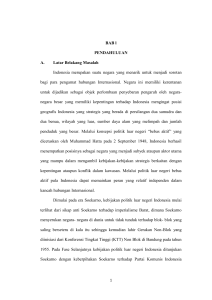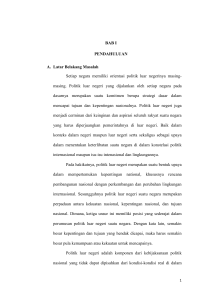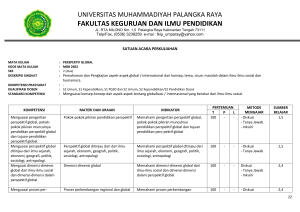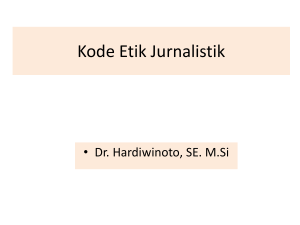Bab 2 Ideologi Media di Indonesia Masriadi Sambo SETIAP
advertisement
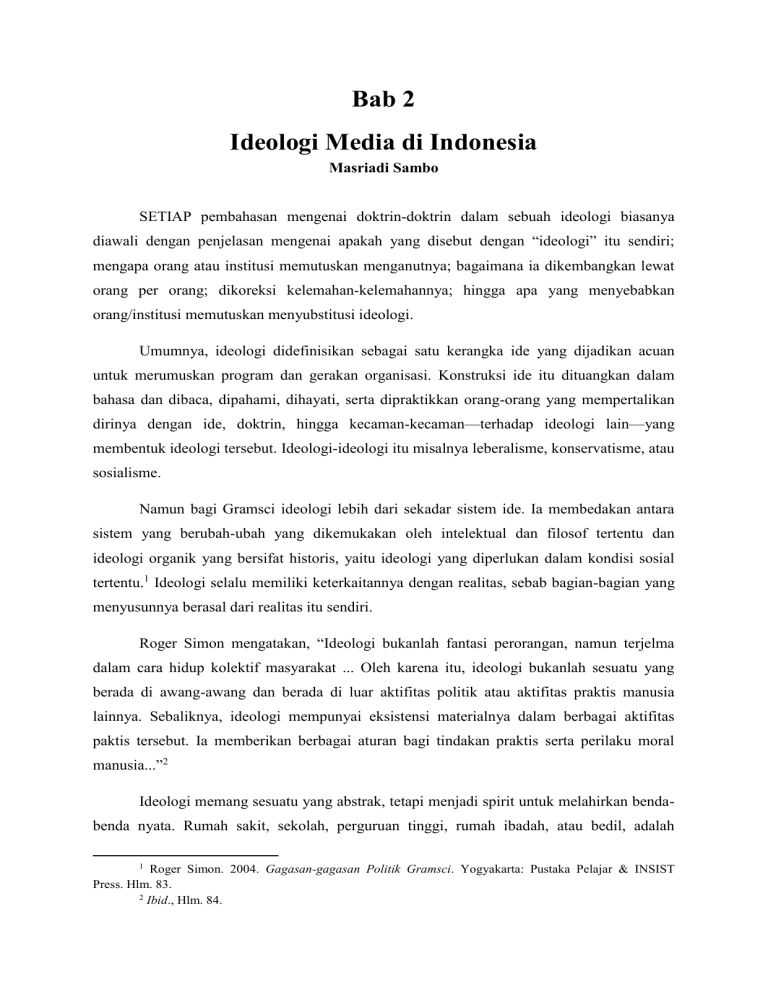
Bab 2 Ideologi Media di Indonesia Masriadi Sambo SETIAP pembahasan mengenai doktrin-doktrin dalam sebuah ideologi biasanya diawali dengan penjelasan mengenai apakah yang disebut dengan “ideologi” itu sendiri; mengapa orang atau institusi memutuskan menganutnya; bagaimana ia dikembangkan lewat orang per orang; dikoreksi kelemahan-kelemahannya; hingga apa yang menyebabkan orang/institusi memutuskan menyubstitusi ideologi. Umumnya, ideologi didefinisikan sebagai satu kerangka ide yang dijadikan acuan untuk merumuskan program dan gerakan organisasi. Konstruksi ide itu dituangkan dalam bahasa dan dibaca, dipahami, dihayati, serta dipraktikkan orang-orang yang mempertalikan dirinya dengan ide, doktrin, hingga kecaman-kecaman—terhadap ideologi lain—yang membentuk ideologi tersebut. Ideologi-ideologi itu misalnya leberalisme, konservatisme, atau sosialisme. Namun bagi Gramsci ideologi lebih dari sekadar sistem ide. Ia membedakan antara sistem yang berubah-ubah yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu dan ideologi organik yang bersifat historis, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu.1 Ideologi selalu memiliki keterkaitannya dengan realitas, sebab bagian-bagian yang menyusunnya berasal dari realitas itu sendiri. Roger Simon mengatakan, “Ideologi bukanlah fantasi perorangan, namun terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat ... Oleh karena itu, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada di luar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas paktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia...”2 Ideologi memang sesuatu yang abstrak, tetapi menjadi spirit untuk melahirkan bendabenda nyata. Rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, rumah ibadah, atau bedil, adalah 1 Roger Simon. 2004. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & INSIST Press. Hlm. 83. 2 Ibid., Hlm. 84. beberapa produk yang dihasilkan karena ideologi mengharuskannya ada. Program-program institusi menjadi bukti atas bisa dinyatakannya ideologi.3 Ideologi bukanlah bahasa yang memenjarakan ide-ide. Setiap ideologi yang terbentuk selalu meminta manifestasimanifestasi. Maka dua proposisi dapat ditarik: (i) pertanyaan tentang ideologi adalah pertanyaan tentang kenyataan; (ii) pernyataan berdasarkan ideologi adalah pernyataan berdasarkan kenyataan. Media adalah salah satu institusi dalam setiap sistem politik. Perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa media bukan hanya institusi dalam sistem politik demokrasi saja. Dalam otoritarianisme pun media hidup. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana ia hidup dan diperlakukan oleh sistem politik yang tengah eksis. Kemudian, yang juga penting disampaikan adalah bahwa media bukanlah institusi polos yang cuma menyebarkan teks informasi kepada khalayak. Bagaimana pun, media adalah institusi politis. Tentu saja pernyataan seperti ini memancing kegusaran. Mereka yang gusar dengan pernyataan seperti ini biasanya alergi dengan istilah “politis” itu. Dasarnya adalah trivialitas dalam memahami politik. Politik melulu dipahami semata dengan hal-hal berikut: “parlemen”, “partai politik”, “politikus”, atau “siasat”. Padahal pernyataan mediamedia sebagai tiang penyangga demokrasi pun sebenarnya sangat politis. Ada keberpihakan di situ, yakni keberpihakan pada demokrasi—dengan prinsip-prinsip universalnya macam keterbukaan atau pencerdasan rakyat. Oleh karenanya, media memiliki ideologi. Omong kosong besar jika ada pemilik media yang mengatakan “kami tidak memiliki ideologi” atau “kami bebas dari ideologi”. Omong kosong yang bisa bersumber dari ketidaktahuan atau semata upaya membodohi publik. Tidak ada satu media pun di dunia ini yang netral dari ideologi. Maka yang menjadi tantangan kemudian adalah memberi definisi ideologi media. Secara sederhana begini: seorang pemilik media adalah pembela teguh kapitalisme, maka media yang dibangunnya akan diarahkan untuk bagaimana memperkuat kapitalisme, membentuk citra baik atas perusahaan-perusahaannya, membela praktik kapitalis secara umum, atau membentuk opini warga bahwa pemerintah memang harus membuka keran investasi swasta yang seluas-luasnya. 3 Bisma Yadhi Putra. 2013. Republik Salah Urat. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hlm. 225. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menyetujui kapitalisme? Mereka membentuk media pula. Ideologinya sosialisme, misalnya. Ide-ide dalam sosialisme dijadikan acuan untuk produksi teks informasi. Misalnya akan diberitakan soal pencemaran lingkungan akibat beroperasinya korporasi tambang, pekerja anak, atau upah yang tidak layak untuk jam kerja berdurasi panjang. Di Indonesia, media progresif macam ini salah satunya adalah tabloib Militan Indonesia. Di luar negeri, misalnya Australia, ada Red Flag. Dengan dua4 contoh di atas, dapatlah “ideologi media” dimaknai sebagai seperangkat ide yang diyakini dan dipakai media untuk menghasilkan corak teks informasi tersendiri yang bertujuan untuk memberitahu publik hingga membentuk kerangka berpikir mereka pula. Ideologi media mengarahkan media untuk mendukung hal-hal tertentu dan menolak hal-hal yang berseberangan dengan apa yang didukungnya. Sebuah media yang mendaulat diri menggunakan demokrasi sebagai ideologi akan membela keterbukaan dan menolak ketertutupan; membela pencerdasan publik dan menentang pembodohan publik; membela kebebasan pers dan menolak pengekangan pers; atau membela hak mengemukakan pendapat dan mengecam seluruh represi untuk merayakan hak tersebut. Soal bagaimana kemudian media memengaruhi pemberitaan, bisa kita lihat dalam kasus pemboman pesawat Iran dan Korea. Pada tanggal 1 September 1983, pesawat pembom Soviet menembak katuh pesawat penumpang Korea 007 yang menewaskan 269 orang. Pada 3 Juli 1988, pesawat penjelajah Amerika, Vincenes, menembak jatuh pesawat penumpang Iran 655 yang melintas di atas Teluk dan menewaskan 290 penumpang. Peristiwanya sama, pelakunya berbeda. Ternyata peristiwa yang sama tersebut digambarkan secara berbeda dalam liputan media-media Amerika. Penembakan pesawat penumpang Korea oleh Soviet diberitakan sebagai suatu pembunuhan atau serangan udara. Liputan pers Amerika banyak memakai kata-kata yang mengutuk peristiwa itu. Kekejaman Soviet diulas dengan liputan yang intens. Tetapi ketika memberitakan jatuhnya pesawat sipil Iran akibat ditembak pesawat Amerika, liputan pers Amerika memiliki gambaran yang berbeda. Penembakan itu tidak digambarkan sebagai pembunuhan, tetapi sebaga kecelakaan atau lebih tepatnya sebagai tragedi. Liputan sama sekali tidak memberitakan mengenai kekejaman Amerika, justru yang ditampilkan adalah kemajuan teknologi radar Amerika. Ilustrasi ini menunjukkan betapa 4 Namun dalam kajian ideologi Gramscian, ideologi-ideologi yang berbeda harusnya tak dilihat dalam perspektif mana yang benar dan mana yang keliru untuk kemudian keputusan penganutan dibuat. Roger Simon menulis: “...ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari ‘kemanjurannya’ dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam peranannnyaa sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial”. Roger Simon, Gagasan-gagasan... Op.cit., Hlm 86. ideologi, kepentingan, dan pandangan masyarakat pers Amerika demikian jauh mewarnai liputan tersebut.5 Perbedaan pemberitaan tersebut tak lepas dari ketegangan kedua negara—Amerika dan Soviet—ketika itu, dalam Perang Dingin, yang didasari pada benturan ideologi keduanya. Berita dibingkai sedekian rupa karena merusak citra institusi penegak ideologi bisa saja memperburuk persepsi khalayak terhadap ideologi itu sendiri. Sampai di sini, setelah uraian singkat di atas, kita akan menganalisis ideologi media di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan ideologi media dalam empat era politik di Indonesia: era penjajahan, era Orde Lama (Orla), era Orde Baru (Orba), dan era reformasi. Termasuk bagaimana ada media yang menyubstitusi ideologi ketika rezim berganti dan ada yang stagnan pada posisi ideologi awal yang ditunjukkan dengan berita-berita yang diproduksinya. A. Ideologi Media di Masa Penjajahan Pada bab sebelumnya sudah disinggung secara singkat perihal bagaimana negaranegara Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia II sekaligus praktik kolonialisme memastikan bahwa media-media di tempat masing-masing memainkan peran politis untuk kepentingan dalam negeri. Melihat politik media negara penjajah yang acap kali menyampaikan informasi-informasi sesat atau pemberitaan subjektif yang merugikan gerakan perlawanan, warga pribumi Indonesia pun melakukan aksi penangkalan dengan mendirikan media-media. Sebagai contoh, setelah Indonesia merdeka dan Jepang kalah perang, Jepang menerbitkan koran yang hendak menghalangi kelancaran roda pemerintahan Indonesia yaitu Berita Gunseikanbu. Kemudian para pelajar Kenkoku Gakuin6 menerbitkan koran Berita Indonesia untuk menyaingi koran terbitan Jepang tersebut.7Yang terlibat dalam hal ini tentu saja mereka yang mendapatkan pendidikan memadai, cakap dalam penulisan, atau aktif dalam kegiatan sosialisasi melek literasi. H. Karomani, “Pengaruh Ideologi terhadap Wacana Berita dalam Media Massa”, Mediator, Vol. 5, No. 1, 2004. 6 Kenkoku Gakuin adalah Perguruan Tinggi Pamong Praja. Sekolah ini didirikan Jepang pada 1944 untuk mendidik para pegawai pemerintah. 7 “Penerbitan Pers Di Masa Penjajahan Dan Awal Kemerdekaan Indonesia”. Lihat: https://mpn.kominfo.go.id/index.php/2012/07/19/penerbitan-pers-di-masa-penjajahan-dan-awal-kemerdekaanindonesia/ 5 Jenis media yang paling populer di masa-masa penjajahan, baik di bawah Belanda maupun Jepang, adalah koran. Di samping itu terdapat beberapa majalah. Yang penting dicatat, kesadaran bermedia warga pribumi adalah hasil dari amatan mereka terhadap praktik bermedia pihak kolonial dan warga (keturunan) China. Hal ini seperti diterangkan oleh Andi Suwirta bahwa “Kelahiran pers bumiputra, yaitu pers yang dikelola, dimodali, dan dimiliki oleh orang Indonesia sendiri, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan pers yang dikelola oleh orang-orang Belanda dan China di Indonesia (Hoogerwerf, 1990:141). Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 orang-orang Belanda dan China itu telah menerbitkan dan memanfaatkan pers sebagai media yang efektif untuk membela kepentingan politik dan sosial mereka. Keadaan seperti itu kemudian disadari juga oleh golongan elite modern Indonesia untuk menerbitkan pers sebagai media untuk menyosialisasikan gagasan, cita-cita, dan kepentingan politik mereka, terutama dalam memajukan penduduk bumiputra di Indonesia.8 Hanya saja, mulanya sifat media-media yang tersebut itu tidak banyak memiliki arti politis, tetapi hanya surat kabar yang lebih banyak memuat iklan-iklan. Berita hanya sedikit. Begitu pula dengan jumlah eksemplar yang hanya berkisar 1.000-1.200. Media-media tersebut seperti Soerabajaasch Advertentieblad yang terbit 1835 di Surabaya atau Semarangsche Advertentieblad di Semarang.9 Tentu saja situasi semacam itu bukanlah hal yang diinginkan para pemilik dan pengelola media. Media pengiklanan bukanlah tujuan mereka. Hanya saja ada beberapa situasi tertentu yang membuat media mereka pada mulanya hanya bisa menerbitkan sedikit berita dan banyak iklan. Pertama, keterbatasan awak. Di masa itu belum orang-orang terdidik yang memiliki kemampuan meliput lalu menulis berita sangatlah sedikit. Sementara untuk membuat media pemberitaan, yakni media yang lebih banyak memublikasikan berita, bukan iklan, dibutuhkan wartawan yang jumlahnya memadai. Kedua, masalah keuangan. Sebagai media baru, tentu faktor keuangan agar tetap dapat hidup sangat penting. Barangkali, suatu strategi pula pada awal penerbitannya media-media tersebut membiarkan banyak iklan agar keuntungan bisa diraup. Pendapatan yang diperoleh pada kemudian hari bisa digunakan untuk merekrut dan membiayai upah para penulis. 8 Andi Suwirta, “Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia”, Mimbar Pendidikan, No.4, 9 “Penerbitan Pers Di Masa Penjajahan...” Op.cit., 1999. Di kemudian hari saat jumlah orang yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas semakin bertambah, semakin banyak pula orang yang dengan kemampuan menulis yang baik. Kemampuan menulis ini dipadukan dengan pengetahuan yang mereka koleksi. Akan tetapi, mereka tidak membentuk media sebagai strategi pergerakan utamanya. Mereka mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan atau intelektual. Dan organisasilah yang kemudian memutuskan membuat media sendiri untuk bermacam kepentingan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Organisasi Budi Utomo, misalnya, menerbitkan surat kabar Darmo Kondo, yang jumlah pembacanya sangat besar di Pulau Jawa. Sementara Sarekat Islam memiliki Oetoesan Hindia. Di samping itu ada media yang penyebarannya dilakukan secara rahasia, seperti Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Termasuk nama penulis artikel di media ini tidak disebutkan.10 Tentu saja tren pembentukan media tidak hanya ada di Jawa. Di Sumatera, beredar surat kabar Sinar Sumatra, Cahaya, Pemberita Aceh, dan Perca Barat. Di Sulawesi beredar surat kabar Pewarta Menado dan Sinar Matahari. Di Kalimantan terbit Pewarta Borneo.11 Dan masih banyak lainnya di berbagai daerah. Meski terpencar di berbagai daerah dan memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, semua media pribumi yang menentang Jepang dan Belanda diikat dalam satu spirit dan ideologi, yakni kemerdekaan. Pembebasan menjadi ideologi, bahwa konstruksi ide yang menjadi landasan bergerak mereka adalah orang-orang di Nusantara berhak mengatur negaranya sendiri, bebas dari perlakukan keji orang asing. Untuk itulah media menyampaikan berita-berita dan artikel-artikel yang ditulis cerdik pandai yang mendukung perjuangan di lapangan, baik dari segi pembangunan moral orang yang berperang, pencerdasan, perkembangan situasi internasional (khususnya mengenai situasi yang dihadapi Belanda dan Jepang dalam Perang Dunia II), dan seterusnya. Menurut Andi Suwirta, “Pers Indonesia, dalam perspektif sejarah, sejak kelahirannya adalah pers perjuangan. Sebutan itu menunjukkan bahwa pers sebagai institusi sosial telah dijadikan senjata oleh golongan nasionalis Indonesia untuk memajukan, mensejahterakan, dan memerdekakan 10 11 bangsanya di satu sisi, serta menentang segala bentuk http://www.artikelsains.com/2014/11/perkembangan-pers-pada-masa-penjajahan.html “Perkembangan Media Cetak Masa Penjajahan dan Kemerdekaan”, Sejarah Negara, 29/9/2014. kesewenangwenangan penguasa yang represif dan otoriter di sisi lain. Cita-cita, gagasan, dan harapan yang tidak pernah hilang dari kesadaran yang sudah menyejarah itu acapkali mengilhami para pekerja pers sekarang untuk terus memelihara, mewarisi, dan mengaktualisasikan idealisme dan etika pers perjuangan itu”12 Di masa itu, ada seorang wartawan bernama M. Tabrani. Ia adalah seorang wartawan yang terkenal. Tulisannya yang banyak menyita perhatian berjudul Ons Wapen (Senjata Kita). Tulisan—yang ditulis tahun 1929—ini berisi refleksi pemikirannya mengenai kaitan antara pers dan kemerdekaan. Ia menegaskan “bahwa pers, bagaimana pun, merupakan ‘senjata kita’ untuk meperjuangkan kemerdekaan Indonesia”. Adalah salah satu tanggung jawab pers untuk membangkitkan kesadaran politik, mendidik masyarakat, dan mengangkat derajat bangsa dari dunia gelap ke dunia terang. Karena itu M. Tabrani mengecam adanya pers yang bersifat “netral” karena kenetralan itu pada gilirannya adalah steril dari kepentingan dan tujuan politik.13 Lantas, seiring dengan membaiknya kualitas media-media lokal, pemerintah kolonial Belanda mulai mengkhawatirkan efektifitas pemberitaan dan agitasi yang dimuat di dalam setiap edisinya. Karenanya pada 1931 pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie yang memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang berbagai publikasi yang dinilai bisa “mengganggu ketertiban umum”. Larangan terbit baru dilaksanakan setelah penerbitan yang bersangkutan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai penerbitan yang dilarang terbit untuk sementara. Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Bahkan bisa diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari berturut-turut.14 Strategi lain untuk menghadang pengaruh politik dari mediamedia Indonesia adalah dengan memberikan subsidi kepada pers yang bersifat netral dan moderat, serta memajukan Balai Pustaka. Badan terakhir itu sejak didirikannya pada tahun 1908 memang ditugasi untuk menyediakan bacaan bagi rakyat agar mereka menjadi warga negara yang baik dalam lingkungan politik kerajan Belanda.15 Maka politik media yang Andi Suwirta, “Zaman Pergerakan, Pers...” Op.cit., Ibid., 14 Reny Triwardani, “Pemberedelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, 2010. 15 Setiadi, 1991:23-46, dalam Andi Suwirta, “Zaman Pergerakan, Pers...” Op.cit., 12 13 dijalankan berseberangan dengan media-media yang menyuarakan kemerdekaan. Hal seperti ini berlanjut ke era pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang setelah berhasil menundukkan Belanda mengubah sejumlah kebijakan terhadap pers secara signifikan. Surat-surat kabar lokal ditutup untuk mengantisipasi propaganda anti-Jepang dan bangkitnya kesadaran melawan. Akan tetapi Jepang tetap memperbolehkan sejumlah koran di kota-kota besar untuk terbit, antara lain Asia Raya (Jakarta), Sinar Baroe (Semarang), Soeara Asia (Surabaya), Kita Sumatera Shimbun (Medan), Atjeh Simbun (Kutaradja). Sementara surat kabar Belanda tidak boleh terbit. Wartawannya ditangkap dan dipenjara. Di samping penutupan, Jepang pun melebur kantor kerita Antara dalam kantor berita milik mereka, Domei. Berbagai kebijakan tersebut tujuannya satu: untuk mendukung pendudukan Jepang di Tanah Air lewat penyebaran propaganda-propaganda.16 Himpitan ini tidak membuat orang-orang yang hendak mendirikan media patah arang. Tak sedikit saat itu media diterbitkan secara rahasia. Cetakan-cetakan yang mereka produksi dibagikan secara terselubung. Namun tentu saja upaya seperti ini tak melulu berjalan mulus. Beberapa orang ketahuan, lalu ditangkap dengan dalih subversif. Ada banyak kelompok perlawanan dalam agresi Jepang. Salah satunya kelompok Pemalang. Kelompok ini bertugas menyebarkan propaganda anti-Jepang dan berita-berita peperangan melalui Menara Merah dan dari mulut ke mulut. Isi Menara Merah mencakup ringkasan berita setempat dan informasi mengenai penindasan Jepang di daerah-daerah lain Pulau Jawa. Menara Merah juga memuat artikel-artikel mengenai ciri atau sifat imperialisme.17 Menara Merah sendiri terbit pada tahun 1939 dengan ukuran saku dan beredar terbatas di kalangan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Dan yang menjadi konten utama Menara Merah adalah artikel-artikel tentang Marxisme dan situasi internasional yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk pemakaian mesin jahit dan iklan-iklan seperti pada kulit mukanya sebagai strategi kamuflase.18 Pengedaran bacaanbacaan yang berisi kutukan terhadap imperialisme dan seruan agar rakyat lebih berani melawan sudah dijalankan sejak 1926. Dari fakta-fakta di atas, dapatlah ditarik sejumlah kesimpulan mengenai ideologi media di era penjajahan Belanda dan Jepang. Pertama, ideologi pembebasan menjadi spirit “Penerbitan Pers Di Masa Penjajahan...” Op.cit., Anton E. Lucas. 1989. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 81. 18 Ibid., Hlm. 74. 16 17 universal semua media yang antikolonialisme ketika itu. Media-media progresif adalah sarana gerakan kebangsaan untuk melawan penjajahan dengan pelbagai metode. Ada gerakan perlawanan bersenjata. Tugas media di sini adalah mengabarkan situasi pertempuran di lapangan. Terlebih ketika ada petinggi militer dari pihak penjajah yang tewas, media-media cukup semangat memberitakannya karena dapat membangkitkan moral atau semangat bangsa. Ada pula perlawanan terrhadap propaganda-propaganda menyesatkan yang disebarkan oleh media-media yang dikuasai oleh pihak penjajah. Di sini terjadi perang propaganda. Bukan hanya berita, propaganda pun disampaikan lewat artikel-artikel. Uniknya, perseteruan melalui tulisan bukan hanya antara penulis (cendekiawan) pribumi dengan penulis (pejabat/militer/cendekiawan) berkebangsaan asing (Jepang dan Belanda), melainkan pula dengan penulis-penulis pribumi yang berkomplot dengan pihak penjajah. Di samping semua itu, ada pula perlawanan di sektor kebudayaan atau sastra. Maka tak bisa diabaikan pula perjuangan para wartawan. Peran mereka dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia pada waktu sangat nyata. Dalam tekanan pemerintah Jepang yang tidak mau melepaskan Indonesia merdeka dan Belanda yang membonceng Sekutu untuk kembali menancapkan kekuasaannya maka pers Indonesia pada waktu itu berdiri dibelakang kaum republikein menyokong terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia sehingga orang menyebut pers republiken . Untuk menandingi tulisan-tulisan yang termuat pada koran republiken, Belanda membuat koran tandingan di antaranya De Courant (Bandung), De Locomotief (Semarang), Java Bode (Jakarta).19 Kedua, di samping ideologi pembebasan, media-media tertentu membonceng ideologi spesifik untuk keperluan politis jangka panjang, yakni memperjuangkan bentuk atau corak ideologi negara setelah merdeka. Jadi misinya bukan hanya terbatas pada perlawanan penjajahan. Dalam catatan sejarah, dikenal media-media yang mengusung ideologi Marxisme. Media ini berperan dalam perlawanan terhadap penjajahan, tetapi menghendaki terbentuknya negara sosialis yang kemudian membangun aliansi internasional dengan negaranegara yang berideologi sama. Media ini meyakini bahwa tidak cukup bala tentara penjajah terusir, karena akar permasalahannya adalah imperialisme global yang dimainkan oleh negara-negara maju. Dengan adanya aliansi, negara bekas jajahan akan kuat dari terpaan tekanan para imperialis. Terlebih setelah Indonesia merdeka, Soekarno naik takhta dengan membawa spirit Marxisme dalam program-program kerjanya. Dan Soekarno pula 19 “Penerbitan Pers Di Masa Penjajahan...” Op.cit., membangun aliansi dengan presiden-presiden yang berpandangan sama, misalnya Fidel Castro. B. Ideologi Media di Era Orde Lama Dalam sejarahnya, media di Indonesia memperjuangkan dua kebebasan. Pertama, kebebasan bangsa dan wilayah dari penjajahan. Upaya ini dilakukan dalam kapasitas media sebagai agen pendidikan politik. Pembebasan bangsa diperjuangkan lewat kata-kata yang menggerakkan nurani dan keberanian untuk melawan. Kedua, kebebasan pers dari kungkungan penjajah dan rezim politik dalam negara yang sudah berdaulat. Yang pertama sudah berhasil diraih. Akan tetapi, ternyata tekanan terhadap pers berlanjut dalam politik yang sudah berubah. Inilah yang dialami media-media yang masih bertahan dalam perubahan politik dari masa penjajahan ke era kemerdekaan Indonesia yang kemudian dipimpin oleh Soekarno. Ada pun Soekarno dikenal dengan rezim diktator yang dijalankannya setelah Indonesia lepas dari belenggu penjajahan asing. Akan tetapi, di awal-awal Soekarno memerintah demokrasi tengah dinikmati sehingga media-media tumbuh. Koran dan majalah sangat mendominasi waktu itu. Sebagian darinya adalah “alat perjuangan partai dan menjadi corong ideologis”. Salah contoh adalah Abadi yang menjadi media resmi Masyumi, Duta Masyarakat milik NU, Harian Rakyat milik PKI, Pedoman milik PSI, dan Suluh Indonesia milik PNI. Dan terhitung 12 tahun setelah proklamasi, ada 116 koran harian terbit, dengan oplah mencapai ratusan ribu per harinya. Ditambah lagi dengan banyaknya surat kabar mingguan. Surat kabar berbahasa Belanda dilarang terbit di tengah booming media tersebut. 20 Jumlah tersebut kemudian merosot signifikan ketika Soekarno mulai bersikap tegas terhadap sumber-sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Media yang tak sejalan dengan jalan (ideologi/kebijakan) politiknya Soekarno akan dimatikan. Dasar politis mengapa kemudian Soekarno bersikap keras terhadap media yang memilih beroposisi adalah keinginannya untuk mewujudkan stabilitas politik untuk mendukung penyuksesan nation building, salah satu proyek revolusi yang digerakkannya. Sumber-sumber kegaduhan akan dimatikan karena dapat mengganggu kelancaran atau konsentrasi agenda tersebut. 20 Oryza A. Wirawan, “Pers dan Presiden: Belajar dari Orde Lama”, Berita Jatim, 24/10/2014. Dapat dikatakan, nation building menjadi karya besar Soekarno. Proyek tersebut “harus diselamatkan, bahkan tidak boleh dirugikan oleh penerapan demokrasi dengan semua prosedurnya”. Soekarno pada waktu membuat pilihan: “Demokrasi untuk Indonesia, ya atau tidak, sekarang atau nanti?”21 Dalam masa pemerintahan Soekarno, masyarakat Indonesia bisa dibuat percaya bahwa demokrasi dapat ditunda kalau ada kepentingan lain yang lebih mendesak, yakni proyek nation building itu.22 Mulanya Soekarno menentang keras sistem parlementer yang sudah pernah diterapkan sebelumnya pada daswarsa 1950-an karena banyak membuat kegaduhan (instabilitas) politik. Ketidakstabilan politik tersebut pertama kali membuat Soekarno bersikap sinis pada sistem parlementer, lalu ketidaksukaannya menjalar pada demokrasi Barat dengan pelbagai muatan-muatan programnya, termasuk soal “kebebasan pers”. Oleh sebab itu, ketika Demokrasi Terpimpin dijalankan, pers mendapatkan tekanan yang kuat. Sistem presidensial yang kemudian diterapkan Soekarno memberi presiden wewenang besar untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Pers yang beroposisi adalah salah satu sumber kegaduhan sehingga perlu dikungkung. Tahun 1954, Persbreidel Ordonnantie dicabut, sebagai salah satu agenda penghapusan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang merugikan penduduk pribumi. Kebijakan Belanda tersebut dibatalkan lewat penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954. Poin utamanya, “Dengan aturan ini, maka sebetulnya hidup matinya surat-kabar tergantung daripada pendapat yang memegang kuasa ini. Mengingat akan dasar negara kita ialah demokrasi, lebih negara demokrasi yang bercorak negara-hukum, sifat-sifat mana menghendaki peperiksaan umum, kesempatan minta peradilan lebih tinggi untuk tiaptiap kali anggota masyarakat diganggu dalam haknya; dan pula karena pasal 19 Undang-undang Dasar Sementara dengan tegas dan dengan penuh mengakui kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dari setiap orang, maka di lingkungan Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementaranya tidak ada tempat lagi untuk terus berlangsungnya aturan yang dimaksud ini”23 Ignas Kleden, “Sejarah Politik Indonesia, Demokrasi yang Tertunda”, Kompas, 22 & 24/5/1999. Munafrizal Manan. 2005. Gerakan Rakyat Melawan Elite. Yogyakarta: Resist Book. Hlm. 3. 23 Baca “Memori Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pencabutan Ordonnantie 7 September 1931 (Staatsblad 1931 No. 394 jo. Staatsblad 1932 No. 44, “Persbreidel Ordonnantie”). 21 22 Pada masa demokrasi terpimpin, pembredelan pers pun berlanjut. Dengan banyaknya pers yang dibredel seakan-akan pencabutan Persbreidel Ordonnantie tahun 1954 tidak berarti.24 Ternyata, perjuangan meraih kebebasan pers belum usai. Media harus menghadapi tekanan lagi dari rezim Soekarno. Maka tak ada jaminan pergantian rezim akan menghadirkan kebebasan pers. Segala bentuk perlakukan terhadap pers adalah hal yang baru bisa dilihat ketika rezim baru sudah terbentuk. Pers akan melihat kebijakan kemediaan penguasa bercorak seperti apa. Di samping itu, media-media yang arah pemberitaannya mendukung stabilitas politik dan kebijakan penguasa dibiarkan hidup, terutama media yang menyediakan halaman khusus untuk tulisan-tulisan Soekarno yang berisi pandangan kebangsaannya. Sebaliknya, media-media yang mendukung pemerintah “akan mendapat pesanan dalam jumlah besar dari kantor-kantor pemerintah. Mereka mendapat kredit untuk membeli mesin cetak dan diprioritaskan untuk ikut serta dalam delegasi ke luar negeri. Sementara media oposisi bernasib sial. Wartawan-wartawannya bisa dipanggil Kejaksaan Agung berkali-kali untuk diinterogasi. Tak jarang, ada harian yang dilarang terbit beberapa hari.25 Maka dapat dibayangkan bagaimana nasib media-media baru—yang belum kokoh posisinya—ketika mengambil jalan berseberangan dengan rezim. Tidak ketinggalan, media-media yang mengusung ideologi komunisme juga ikut meramaikan era Orde Lama. Media-media seperti ini biasanya banyak berisi kutukan terhadap imperialisme dan memberitakan upaya-upaya para imperialis untuk menyingkirkan Bapak Proklamator tersebut. Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa media-media di masa penjajahan digagas oleh organisasi-organisasi intelektual. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa kemudian media-media komunis masih tetap bertahan meski gerakan tersebut ditumpas habis-habisan oleh Belanda. Akar sejarahnya dapat kita lacak kembali pada tahun 1926. Pada akhir 1926, gerakan komunis melakukan pemberontakan di Jawa Barat, disusul pada tahun berikutnya di Sumatera Barat. Tekanan dari gerakan ini membuat pemerintah kolonial bertindak yang lebih represif. Ketetapannya: segala gerakan perlawanan wajib dihancurkan! Yang tertangkap akan dibuang ke Boven Digul. Memang pemberangusan ini terbukti efektif dalam melumpuhkan gerakan-gerakan berideologi komunisme, tetapi nyatanya tidak melenyapkan pengaruhnya. 24 25 Reny Triwardani, “Pemberedelan Pers di Indonesia...” Op.cit., Oryza A. Wirawan, “Pers dan Presiden...” Op.cit., Sejumlah besar anggotanya kemudian mencari tempat berteduh di dalam kelompokkelompok yang bersikap lebih nasionalistis-radikal. Ada PNI-nya Soekarno yang menjalin hubungan erat sekali dengan golongan-golongan kiri. Juga dengan Perhimpunan Indonesia.26 Secara umum, memang propaganda dan pelumpuhan terhadap pers yang berseberangan merupakan ciri penting dari rezim-rezim komunis. Uni Soviet, misalnya, negara kuat yang masih bertahan ketika Soekarno berkuasa, bukan hanya menjalankan sebuah sistem sensor yang kaku atas media. Pemerintahnya juga mendorong sebuah kebudayaan jurnalistik yang mensyaratkan dukungan total pada ideologi dan kebijakankebijakan dari partai komunis, yakni Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza.27Media cetak dan media penyiaran audio/video digunakan oleh otoritas-otoritas Soviet, di mana muatan-muatan media tentu saja tak akan menyimpang dari kebijakankebijakan negara pada setiap masa dalam sejarah Uni Soviet.28 Ideologi adalah panutan bagi setiap institusi. Ketika institusi dihancurkan, tidak dapat dipertahankan, para penganut ideologi akan mencari institusi lain atau mendirikan yang baru. Dengan ini pengaruh bisa terus dihidupkan. Koran-koran besar nasional, utamanya pada halaman 1 dan 2, menyediakan rubrik bertajuk “Adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno”. Sampai kemudian situasinya berbalik, di mana media-media yang sebelumnya memuja Soekarno beralih menyerangnya. Steven Handoko menjelaskan hal ini dalam artikelnya yang berjudul “Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru”: “Setelah Gerakan 30 September ditumpas, media masih menjadi pembela Soekarno. Kolom “Adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno” masih menghiasi halaman pertama atau kedua surat kabar nasional. Ini masih berlanjut hingga tahun 1966 ... Pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 1966, para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan konferensi kerja di Pasir Putih, Jawa Timur. Jenderal Soeharto memberikan sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pangdam VIII Mayjen Sumitro. Dalam sambutannya, Soeharto memuji PWI sebagai patriot Indonesia dalam menjaga moral Pancasila. Soeharto mengamati kemerdekaan pers dalam Orde Lama disalahgunakan sebagai alat teror psikologis terhadap pendapat P.J.A. Idenburg, “Jawaban Belanda atas Nasionalisme Indonesia”, dalam H. Baudet dan I.J.Brugmans. 1987. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: YOI. Hlm 149-150. 27 Andrew Heywood. 2014. Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 338. 28 Ibid., 26 yang berbeda atau bertolak belakang ... Setelah deklarasi dari wartawan disampaikan, pers mulai kritis terhadap Soekarno. Duta Masjarakat memuat kolom ‘Adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno’ yang terakhir pada 21 Oktober 1966. Dalam kolom ‘Djangan Dianggap Enteng’, Duta Masjarakat mengkritik Bung Karno yang membangun hotel-hotel megah di tengah kemelaratan rakyat. Demokrasi Terpimpin adalah dalih untuk mendiamkan suara rakyat, revolusi adalah alasan untuk menghamburkan uang negara ... Setelah Soekarno disingkirkan, media sudah tidak lagi menyediakan kolom khusus bagi presiden. Bapak Negara atau Pemimpin Besar Revolusi itu disingkirkan dari halaman utama surat kabar di seantero negeri”29 Ideologi media di era Orde Lama masih menempatkan “kebebasan” pada tempat teratas bangunan ide yang menjadi panduan dalam menghasilkan teks-teks pembentuk opini atau kesadaran umum. Tampak bahwa media bahkan masih lebih memilih memperjuangkan idealitas tersebut, yang berarti harus mengonrbankan pengkultusan Soekarno secara personal. Sikap berbalik arah yang ditempuh media-media tersebut adalah puncak kejemuan akibat pengekangan untuk mengekspresikan teks-teks berbasil ideologi keadilan sosial yang dibawa media-media tersebut. Dengan mengusung ideologi keadilan sosial, media-media sebetulnya berkeinginan untuk menyorot fenomena kemiskinan yang menjamur di masyarakat, korupsi di institusiinstitusi negara, dan sebagainya. Dan ketika Soekarno berhasil dilemahkan, lalu dijatuhkan, media-media tersebut merasakan adanya angin surga kebebasan pers. Di sini, suatu harapan adanya perlakuan yang baik terhadap pers sedang dibayangkan. Langkah awalnya, media, dengan persatuan resmi wartawan-wartawannya, harus mendukung pergantian kekuasaan terlebih dahulu. C. Ideologi Media di Era Orde Baru Orde Baru bukanlah sebuah tatanan politik yang terbentuk secara alami. Tatanan politik ini bukanlah hasil dari bekerjanya hukum alam untuk mengatasi ketidakseimbangan atau kekacauan yang terjadi pada tatanan politik sebelumnya. Orde Baru adalah hasil dari rekayasa politik yang mempraktikkan hal-hal baru tapi ternyata masih mewarisi cacat-cacat pada rezim sebelumnya. 29 Steven Handoko, “Soekarno di Balik Jeruji Media Orde Baru”, Remotivi.or.id, 1/10/2015. Dalam sejarahnya, Orde Baru hadir untuk memuluskan penetrasi kapitalisme ke Indonesia. Dalam Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, David Ransom mengatakan, “Dengan jatuhnya Sukarno yang memiliki nasionalisme tinggi, pemerintah baru berkesempatan membuka lebar-lebar kekayaan alam Indonesia yang luas itu bagi perusahaanperusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat. Untuk memuluskan masuknya pihak asing tersebut, dibentuk ‘Team Istimewa’ di pemerintahan Indonesia yang terdiri atas menteri-menteri yang menguasai bidang perekonomian, yang oleh ‘orang dalam’ sendiri dikenal sebagai ‘The Berkeley Mafia’ (para Mafia dari Universitas Berkeley). Para ahli dan sarjana lulusan Universitas Call-ifornia tersebut berfungsi sebagai kelompok yang duduk dalam dewan penguasa. Orang-orang inilah yang kemudian membentuk ‘politik nasional baru’ dari rezim yang baru tersebut”30 Akan tetapi, meski aliran modal ke dalam negeri cukup bebas dan deras ketika diberlakukannya liberalisasi, rupanya ini tidak dibiarkan menyentuh aspek kebebasan pers. Baik media-media yang rendah hingga sangat kuat pengaruhnya sama-sama akan direpresi oleh negara. Dalam hal ini, Munafrizal Manan membuat kesimpulan yang benar sekali: “Orba bukanlah antitesis Orla. Keduanya hanya bertolak belakang dalam soal kebijakan ekonomi. Tetapi, untuk politik otoritarianisme dan monopolistik, Orba adalah penerus Orla yang setia lagi kreatif”.31 Sama halnya dengan pada era Soekarno, mula-mula media masih menikmati kebebasan berekspresi di era Orba. Barulah kemudian ketika Soeharto yang juga menggilai stabilitas politik seperti Soekarno mulai melihat kontrol dari media sangat mengganggu, ia melakukan yang sebaliknya, mengontrol media. Mula-mula, yang dilakukan Soeharto adalah membersihkan segala hal yang berbau Soekarnoisme, mulai dari media-media Kiri, pejabat-pejabat pemerintahan, hingga tindakantindakan ideologis untuk melenyapkan segala antitesis kapitalisme. Tidak ketinggalan di dalam tindakan ini ia memberangus pula media-media yang di masa-masa krisis rezim Orde Lama masih setia bersama Soekarno. Meskipun kemudian Soeharto juga bersikap keras terhadap media-media yang pernah mendukung pergantian rezim. 30 David Ransom. 2006. Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia. Jakarta Selatan: KAU. Hlm. 23-24. 31 Munafrizal Manan. Gerakan Rakyat... Op.cit., Hlm. 61. Oktober 1965 adalah awal dari itu semua. Para jurnalis dilucuti dari media. Mediamedia pun dibabat habis. Sebagai akibatnya, dua konsekuensi muncul. Pertama, punahnya media kiri yang praktis kemudian membuka jalan bagi masuk-berkembangnya media yang memilki kencenderungan politik kanan. Kedua, dampak ini merupakan keniscayaan dari dampak pertama. Penumpulan afiliasi politis media secara serta-merta menciptakan pergeseran orientasi ideologis media ketika itu, yakni birokrasi dan pasar. Terjadi pilihan bagi media yang hidup pada masa Orde Baru ketika itu, mati atau terus hidup tetapi berada dalam belenggu birokrasi Orde Baru. Tampak jelas bahwa “pergantian rezim dari era Sukarno ke Orde Baru seolah menandai bergesernya arah politis-ideologis media di Indonesia. Pelumpuhan afiliasi politik kiri media pada masa Orde Baru secara serta merta membabat media yang terikat dan teridentifikasi patronase politik dan ideologi kiri”.32 Empat tahun setelah Soeharto resmi berkuasa, Goenawan Mohamad, Yusril Djalinus, dan beberapa rekan mereka lainnya mendirikan majalah yang diberi nama Tempo. Majalah yang memakai moto “Enak Dibaca dan Perlu” ini terbit seminggu sekali, memuat bermacam berita dari soal politik, hukum, dan sebagainya. Tempo tidak berafiliasi dengan rezim Orde Baru. Sebaliknya, media ini menerbitkan berita-berita kritis yang membikin Soeharto beserta jajarannya naik darah. Karena kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintah dan Golkar membuat penguasa gerah, alhasil pada 1982 Tempo dilarang terbit sementara karena memberitakan peristiwa kerusuhan kampanye pemilu di Lapangan Banteng.33 Setelah diperbolehkan beroperasi kembali, ternyata berita-berita yang menguak kebobrokan rezim Soeharto yang diterbitkan Tempo makin “parah”. Sampai akhirnya Tempo dibredel kembali pada 1994 akibat kemarahan besar Soeharto atas pemberitaan kritis soal mark-up anggaran dalam pembelian 39 kapal bekas dari Jerman Timur. Tempo terbit kembali setelah Soeharto tumbang dari kursi kekuasaan. Selain majalah Tempo, media-media yang dibredel Orde Baru karena dianggap tak bersedia berjalan dalam koridor ideologi penguasa adalah Koran Jurnal Ekuin (dilarang terbit sejak 1983), Expo (1984) Topik (1984), Fokusi (1984), Sinar Harapan (1986), Detik (1994), 32 Azhar Irfansyah dan Nella A. Puspitasari. Tentang Pasang Surutnya Badai Itu: Riwayat Pers Kiri di Indonesia (Bagian II). Indoprogress. 21/5/2014. 33 Reny Triwardani, “Pemberedelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2, 2010. Editor (1994), dan lain-lain.34 Di samping itu media-media tersebut memasabodohkan soal “pemilihan kata pada masa Orde Baru dilakukan dengan berhati-hati dan menyusunnya dengan apik sehingga tidak menyinggung rezim yang sedang berkuasa” 35 yang sangat diperhatikan oleh media-media yang sangat lembek di hadapan kekuasaan sehingga bersedia menerima kompromi agar tidak dibredel. Demokrasi, sebagai ideologi besar yang dibawa media-media nonafiliasi saat itu, sudah diketahui umum salah satunya memuat spirit transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Dalam pada itu ia juga menuntut kebolehan menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan negara. Dan manakala negara tidak sejalan dengan spirit ideologi media ini, maka ada pelumpuhan yang akan dilakukan. Bukan hanya Tempo, salah satu lainnya yang lantang soal ketidakadilan sosial di era Orde Baru adalah koran Indonesia Raya. Koran ini terbit dalam dua periode: 1949-1958 (masa Orde Lama) dan 1968-1974 (masa Orde Baru). Kelahiran surat kabar ini dimulai dengan edisi 29 Desember 1949, dua hari setelah penandatanganan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mengalami lima kali pembredelan singkat selama masa Orde Lama, pembredelan keenam kali menghentikan penerbitan harian ini pada edisi 10 September 1958. Kemudian pada 30 Oktober 1968, Indonesia Raya terbit kembali. Sampai akhirnya dibredel lagi, setelah terbit edisi “penutupan” pada tanggal 21 Januari 1974.36 Ideologi media yang diusung tercermin dalam berita-berita serta tajuk rencana-tajuk rencana yang dimuatnya. Dalam hal pemberitaan tentang kesenjangan sosial dan strategi pembangunan ekonomi, kepedulian koran Indonesia Raya sudah jelas: memberikan perhatian terhadap kepentingan umum, kepentingan rakyat, penegakan hukum, pemenuhan hak asasi, perlindungan atas orang papa, penegakan martabat bangsa, dan kebebasan manusia.37 Posisi Indonesia Raya dalam agenda pembangunan ekonomi Orde Baru adalah bersikap kritis. 34 Khusus untuk pembredelan Tempo, Detik, dan Editor, di sejumlah kota muncul gelombang aksi protes. “Protes paling keras atas tindakan pemerintah berasal dari sebagian kelas menengah perkotaan. Di Indonesia, fenomena ini pertama kalinya terjadi, sebab sebelumnya kelas menengah dianggap apatis pada politik. Aksi itu dibangkitkan oleh kesadaran akan hak untuk mengakses informasi yang bebas dan independen”. Lihat: Munafrizal Manan, Gerakan Rakyat... Op.cit., Hlm. 69-70. 35 Azhar Irfansyah dan Nella A. Puspitasari, “Tentang Pasang Surutnya...” Op.cit., 36 Mochtar Lubis. 1997. Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya. Jakarta: YOI. Hlm. xvii-xviii. 37 Ignatius Haryanto,2006, Indonesia Raya Dibredel!, Yogyakarta: LKiS. Hlm. 98-100. Konsep pembangunan ekonomi yang dimengerti para pengasuhnya dengan para penguasa dan teknokrat Orde Baru adalah hubungan diametral. Mengenai metode pembangunan ekonomi mana yang Indonesia Raya yakini bisa dilihat dalam salah satu tajuk rencana berikut: “Satu, ahli ekonomi yang belajar di Amerika Serikat. Mereka menganjurkan pemakaian teknologi yang capital intensive yang paling modern berdasarkan perhitungan economics of sclae. Dalil yang mereka ajukan adalah bahwa insdustriindustri serupa ini, meskipun tidak akan menghidupkan banyak tenaga buruh, akan dapat mendorong kemajukan ekonomi yang cepat akibat daya produksinya yang besar dan juga dapat bersaing dengan industri-industri internasional. Ada kelompok ahli ekonomi lain yang ingin mengembangkan labour intensive, tanpa meninggalkan mesin-mesin sama sekali karena akan meringankan beban penderitaan rakyat akibat pengangguran luas...”38 Indonesia Raya mantap menempatkan diri pada metode pembangunan ekonomi yang terakhir itu karena dipandang lebih tepat untuk strategi pembangunan ekonomi bangsa. Metode tersebut mengutamakan manusia, yang nasibnya bergantung dari aktivitas kerja. Sementara pengutamaan mesin untuk mencapai volume produksi yang besar semata akan mengubur ribuan hingga jutaan orang ke dalam lubang kenestapaan ekonomi. Terlebih banyak sumber-sumber daya yang belum digunakan dengan maksimal, baik sumber alam maupun manusianya. Begitulah gambaran perseteruan ideologis antara media-media kritis dengan penguasa, juga dengan media-media yang bersedia berkomplot dengan rezim. Dalam pertarungan ini, ada media yang gugur alias tak terbit lagi hingga kini. Awak jurnalisnya mengambil kesempatan lain dengan bergabung dalam media-media lain. Sebaliknya, mediamedia yang masih bertahan, atau yang berhenti terbit sampai Soeharto jatuh tapi kemudian para pengelolanya dulu sepakat menghidupkannya lagi, seperti dalam kasus majalah Tempo, akan menikmati angin kebebasan pers yang sesungguhnya di orde selanjutnya, sebuah tatanan yang kemudian dikenal dengan istilah “Era Reformasi”. Bahkan di era ini, media-media kiri pun bisa leluasa menyalakan api perlawanan kembali. 38 Ibid., D. Ideologi Media di Era Reformasi Tentu saja Era Reformasi masih berisi tragedi-tragedi penyerangan terhadap (awak) media seperti yang pernah terjadi di tiga era sebelumnya. Meski jumlahnya menurun dan ada penegakan hukum yang jelas atas kasus-kasus yang terjadi. Buku Jejak Darah Setelah Berita39 yang disusun Abdul Manan dan Sunudyantoro mencatat salah satu peristiwa tragis tersebut. Buku ini menceritakan sepak terjang seorang wartawan bernama Prabangsa yang bekerja di media Radar Bali—sejak 2003. Akan tetapi Prabangsa adalah wartawan di dua orde: Orde Baru dan era reformasi. Ia udah menjadi wartawan sejak tahun 1995, dengan memulai karier di Harian Nusa. Di Radar Bali, ia sering menulis berita-berita yang terjadi di Kabupaten Bangli, kampung halamannya. Beberapa yang dianikkannya adalah berita dugaan korupsi pembangunan fasilitas pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli senilai Rp 4 miliar. Setelah pemberitaan tersebut, kepada rekan-rekannya Prabangsa mengaku pernah beberapa kali diancam orang tak dikenal. Hingga pada suatu hari ia menghilang dan pembunuhan terhadapnya tercatat terjadi pada 11 Februari 2009. Ia dibawa ke sebuah rumah yang pembangunannya belum rampung, dipukuli oleh beberapa orang, lalu dalam keadaan sekarang ia dibuang ke laut. Saat ditemukan, jenazah Prabangsa sudah rusak. Pada Mei 2009, polisi menetapkan enam tersangka pembunuh Prabangsa. Aktor intelektual dari pembunuhan tersebut adalah Nyoman Susrama, adik kandung Bupati Bangli. Kasus tersebut menampakkan bagaimana era baru ini tak sepenuhnya bisa menjadi “surga” bagi para jurnalis. Ternyata pemain politik dalam sistem demokrasi tidak menghormati demokrasi secara umum, dan secara khusus tidak menghormati institusi demokrasi (media) yang hidup dan bergerak dengan ideologi demokrasi, bahkan turut berperan menghidupkan, menggerakkan, hingga mengembangkan demokrasi itu sendiri. Represi terhadap (ideologi dan awak) media hanya mengonfirmasi tesis Larry Diamond berikut: “Bentuk ideal demokrasi tidak mampu dipenuhi sekalipun oleh negara-negara demokrasi liberal. Bahkan negara (demokrasi liberal) yang memiliki kadar liberal 39 Abdul Manan dan Sunudyantoro, Jejak Darah Setelah Berita, Jakarta Pusat: AJI. lebih rendah menghadapi persoalan serius berkenaan dengan jaminan kebebasan pribadi dan berserikat ... Tegasnya, tak ada negara modern yang mampu menerapkan demokrasi secara sempurna, dengan kepemilikan sumber-sumber daya politik yang kira-kira setara di antara semua warga negara dan dengan pemerintahan yang sepenuhnya atau hampir sepenuhnya bersikap responsif terhadap segala macam tuntutan”40 Akan tetapi, era ini lebih condong kepada suasana positif bagi perkembangan pers. Kebebasan pers lebih besar ketimbang jumlah kejahatan terhadapnya, berbanding terbalik dengan tiga orde yang telah diulas di atas. Era reformasi adalah rumah yang nyaman bagi media. Hanya saja sesekali ada pihak-pihak yang hendak merampok rumah tersebut, merampok hak media untuk bebas mengekspresikan ideologinya. Bentuk pemerintahan yang baik adalah yang bersedia memberi keleluasaan bagii media untuk merayakan ideologi apa saja, dengan asumsi seperti yang telah disebutkan pada bagian awal bab ini, bahwa ideologi tak bisa dinilai dari benar-salahnya melainkan dari kemanjurannya. Lebih dari itu, bentuk pemerintahan yang terbaik adalah yang bersedia mempertahankan situasi kemediaan seperti itu dan memberinya garansi agar tetap terjaga secara konstitusional. Inilah yang kemudian berlangsung setelah Soeharto tumbang dan reformasi kemudian bergulir. Sebuah tatanan politik terbuka telah tercipta. Kebebasan berpendapat mula-mulai dianggap barang baru, lalu kemudian publik menjadi terbiasa. Seiring dengan tumbuh pesatnya jumlah media, serta publikasi-publikasi (berita, artikel, esai) kritis yang ramai mewarnai kehidupan politik rakyat Indonesia sehari-hari. Kebebasan pers, yang spiritnya bersumber dari ideologi pembebasan, yang sudah diperjuangkan lebih dari tiga dasawarsa. Setelah dicekik oleh pemerintah kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru, media kemudian bisa bernapas kembali dengan ideologi yang dikehendakinya. Trauma politik masa lalu telah melahirkan kesadaran bahwa demokrasi adalah pilihan yang tidak bisa ditawar lagi jika tidak ingin mengulangi kembali tampilnya 40 Larry Diamon. 2003, Developing Democracy: Toward Consolidation, Yogyakarta: IRE Press. Hlm. 3-4. Atau kita bisa lebih optimis dengan kesimpulan yang agak longgar dari Juan J. Linz: “Demokrasi politik tidak selalu menjamin, bahkan dalam suatu kewajaran sekali pun, adanya masyarakat yang demokratis, yaitu suatu masyarakat yang menjamin kesetaraan peluang yang cukup besar di semua aspek kehidupan” (Juan J. Linz, 1978, The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration, Baltimore: John Hopkins University Press, Hlm. 97. rezim ototritarian di Indonesia.41 Apa yang diberikan demokrasi adalah jaminan kebebasan yang tak tertandingi oleh sistem politik apa pun.42 Di saat inilah media memiliki kekuasaan politik, yakni terutama dalam hal mengontrol negara. Media menjadi “anjing penjaga” di era reformasi. Pada tiga era sebelumnya, media-media dikontrol dengan cukup ketat oleh rezim. Sementara di era reformasi, yang menggaungkan demokrasi sebagai landasan pembangunan negara, terjadi pembalikan politis menjadi “kontrol pers terhadap negara”. Mulai dari menyebarkan pesan politik yang seharusnya diketahui warga, sampai bagaimana media mampu membentuk opini publik dalam skala yang lebih luas karena tak lagi ditekan sistem. Kesepakatan untuk berdemokrasilah yang menjadi dasar mengapa tatanan yang baik ini bisa terwujud. Secara instrumental, demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara. Pertama, pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, oposisi, serta ‘hak-hak politik mendasar semacam ini tidak mungkin hadir tanpa pengakuan terhadap kebebasan sipil yang lebih luas. Kedua, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri. Ketiga, demokrasi mendorong otonomi moral, yakni kemampuan setiap warga negara membuat pilihan-pilihan normatif, dan karenanya pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk memerintah sendiri. Pendek kata, proses demokratisasi mendorong upaya menberdayakan kemanusiaan (menumbuhkan tanggung jawab pribadi dan kecerdasan) sembari menyediakan sarana terbaik bagi rakyat untuk melindungi dan memajukan kepentingan bersama”.43 Pluralisme ideologi media Dalam konteks etnisitas, demokrasi menganjurkan satu solusi: pluralisme. Tekanan ini bermaksud untuk menciptakan suatu sistem sosial di mana mereka yang berbeda-beda identitas kultural dan religositasnya bisa saling menghormati atau menghargai. Maka bermuncullah bermacam entitas kebudayaan di situ. Ketika pluralisme ini dibawa ke dalam kehidupan media, perdebatan serius muncul. Sebab pada saat demokrasi, tatanan politik yang tengah kita jalani kini, meleluasakan 41 42 Munafrizal Manan, Gerakan Rakyat... Op.cit., Robert Dahl, 1989, Democracy and Its Critics, New Haven: Yale University Press, Hlm. 88-89. 43 Larry Diamon, Developing Democracy... Op.cit., keberadaan dan operasi media, saat itu juga ia harus mengakui sejumlah media yang tidak sejalan dengan demokrasi itu sendiri. Era reformasi tak hanya ditandai salah satunya dengan tumbuh pesatnya jumlah media, tetapi diwarnai pula oleh ramainya ideologi media yang saling berbeda-beda. Sebelum kita mendiskusikan bagaimana polemik ideologi media di era reformasi ini muncul, perlu kiranya dipaparkan sejumlah contoh media dengan ideologi khas yang diusungnya, lalu bagaimana mereka hidup di tengah tren kapitalisme media di mana modifikasi “fakta” dimainkan untuk kepentingan rating atau profit. Pertama, media dengan ideologi Kiri. Media Kiri adalah media yang menggunakan ideologi Marxisme, sosialisme, komunisme sebagai ideologinya. Media semacam ini biasanya bersifat progresif, yakni kerap menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap praktikpraktik kapitalisme. Jika muncul isu upah minimum, misalnya, media Kiri berpihak pada tuntutan para buruh agar upah dinaikkan dan berbagai tunjangan harus dipenuhi oleh perusahaan. Secara umum, baik berita, editorial, maupun artikel-artikel yang diterbitkan dalam lingkup antikapitalisme dan bagaimana tatanan sosialis terwujud. Berikut beberapa media Kiri yang saat ini dapat kita temui: 1. Militan Indonesia Media ini menentang keras para kapitalis dengan sistem yang mereka puja, kapitalisme. Secara tegas dinyatakan sikap: “Seiring dengan menuanya kapitalisme, ia justru menjadi sistem yang menghambat kemajuan masyarakat secara umum. Kaum borjuis sudah kehilangan nilai-nilai progesifnya sama sekali. Masalah-masalah ekonomi, sosial, dan politik sudah tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Kontradiksi utama kapitalisme adalah bahwa produksi dilakukan secara sosial (yakni oleh mayoritas kaum pekerja) tetapi nilai-lebih produksi tersebut (profit) diambil secara pribadi (yakni oleh segelintir pemilik modal). Penyelesaian kontradiksi ini adalah dengan menyerahkan nilai-lebih produksi ke rakyat pekerja dengan cara menasionalisasi ekonomi di bawah kontrol demokratis rakyat pekerja yang akan merencanakan ekonomi secara sistematis dan demokratis untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk laba dan profit semata”.44 44 Baca lebih lengkap di: http://www.militanindonesia.org/mengenai-militan.html Media juga mendukung demokrasi. Akan tetapi berbeda sama sekali dengan demokrasi kapitalistis yang banyak digunakan sebagai ideologi oleh media-media oportunis. Konsep yang dianut adalah “demokrasi rakyat pekerja”. Penjelasannya: “Demokrasi adalah oksigen dari sosialisme. Tidak akan ada sosialisme yang sejati tanpa demokrasi kelas pekerja. Perubahan sistem ekonomi kapitalisme ke sosialisme juga harus disertai dengan perubahan struktur politik di dalam masyarakat secara radikal. Kita harus merubah demokrasi yang kita miliki sekarang ini, yakni demokrasi borjuis yang hanya menjamin hak-hak demokrasi kaum pemilik modal dan antek-anteknya, menjadi demokrasi rakyat pekerja”.45 2. Berdikarionline.com Berdikari adalah media yang cukup kritis menyorot berbagai masalah pembangunan, dampaknya terhadap masyarakat kecil seperti petani, juga bagaimana para pemodal mengeruk untung dari praktik pembangunan tersebut. Berdikari memakai moto: “Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”. Tidak lupa pula media ini cukup sering memublikasikan tulisan-tulisan mengenai pemikiran Soekarno, di samping menerbitkan sejumlah tulisan Soekarno sendiri. 3. IndoPROGRESS Media ini menyita perhatian banyak pihak, terutama akademisi dengan latar ilmu sosial dan ilmu ekonomi, karena banyak menghasilkan tulisan-tulisan bernas mengenai konsep ekonomi politik, Marxisme, tokoh-tokoh gerakannya, hingga membahas berbagai macam persoalan publik dengan perspektif Kiri. Ada pun pernyataannya adalah sebagai berikut: “Sejak jatuhnya rezim kediktatoran militer Orde Baru, kita memasuki satu periode yang ditandai oleh kekayaan yang makin terpusat di tangan oligarki, kian melebarnya jurang kaya-miskin, akses terhadap kebutuhan dasar publik yang semakin memburuk, dan tingkat pendapatan yang terus jatuh di hadapan laju peningkatan barang kebutuhan pokok ... Rakyat dikebiri representasi politiknya, sekaligus tak punya akses ke sumberdaya ekonomi. Walhasil, kebebasan politik yang ada tak memiliki sumbangan apapun bagi peningkatan kesejahteraan, sehingga yang muncul adalah apatisme dan 45 Ibid., aktivitas politik yang reaktif, bahkan menjurus barbar. Dalam medan ekonomipolitik seperti itu, IndoPROGRESS menawarkan ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman politik praktis dalam bingkai besar gerakan antikapitalisme. Kami percaya bahwa perjuangan melawan sistem kapitalisme, pada akhirnya adalah sebuah perjuangan politik yang konkret dari rakyat pekerja, yakni buruh, petani, dan kalangan miskin perkotaan, untuk membebaskan dirinya dari penindasan kapital. Namun dalam perjuangannya itu, rakyat pekerja tidak hanya berkonfrontasi secara langsung dengan kapital, tetapi sering sekali mereka harus menghadapi konflik-konflik bernuansa etnisitas, ras, agama, militerisme, nasionalisme sempit, hingga ketidakadilan gender dan seksual akibat dominasi paham patriarki dalam masyarakat. Di dalam pusaran konflik-konflik ini, tidak jarang rakyat terseret ke dalam arus konflik yang menjauh dari perlawanannya terhadap kapital, sehingga seringkali rakyat pekerja menganggap bahwa itulah konflik yang sesungguhnya”.46 4. Islam Bergerak Berbeda dengan tiga media di atas, Islam Bergerak lebih menekankan aspek ajaran Islam dalam sikap progresif. Misalnya, media ini mengkaji bagaimana Islam memandang gerakan buruh (perempuan) yang membawa sejumlah tuntutan tertentu. Juga di sini diangkat persoalan fikih, seperti dalam menjelaskan persoalan agraria.47 Munculnya media-media Kiri baru ini tentu menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin sebuah ideologi yang telah ditundukkan secara sistematis dan segala hal yang berkaitannya dengannya didekonstruksi oleh negara masih bisa muncul di kemudian hari dengan institusi yang berbeda? Diperlukan penjelasan khusus untuk ini. Setiap ideologi tak lantas mati ketika institusi atau superstruktur yang menjadi representasi atasnya hancur. Keruntuhan institusi representasi ideologi tak mematikan ideologi sebab individu-individu yang mengidentifikasikan diri sebagai penganut ideologi 46 47 Selengkapnya lihat: http://indoprogress.com/tentang-kami/ Lihat artikel: “Dalil Perjuangan Agraria”, Islam Bergerak, 24/12/2015. masih konsisten menganut dan mengaplikasikannya dalam aksi-aksi nyata.48 Lagian, menganut ideologi dan kepercayaan terhadap suatu institusi yang memakai ideologi tersebut tidak bisa melulu dicampurkan. Dalam konteks Marxisme, seseorang yang menganutnya belum tentu setuju dengan PKI, misalnya, karena dinilai ada strategi-strategi gerakan yang tidak sesuai. Mereka yang berada di luar institusi ideologi juga berperan terus menghidupi ideologi. Loyalitas rakyat atas ideologi belum tentu tereduksi ketika negara mereka beralih ideologi. Ideologi tak terkurung dalam sekat-sekat administrasi institusi, tetapi terikat pula di dalam benak individu-individu yang otonom atas institusi. Ideologi bekerja dalam lima fase: (i) fase pembangunan ideologi. Di sini ideologi dibentuk menjadi sebuah bangunan pikir atau suatu kepercayaan. Penggagasnya menuliskan landasan-landasan aksi yang menjadi tuntutan ideologi sebagai sebuah manifesto. Literaturalisasi ideologi penting untuk menjadikannya tetap bisa diakses ketika tak ada lagi individu atau lembaga yang menyiarkannya secara lisan; (ii) fase doktrinasi. Penggagas ideologi menyuntik doktrin-doktrin ideologi kepada individuindividu sebagai “sasaran ideologi”. Terdapat pula individu-individu yang tak mengalami doktrinasi ideologi bukan lewat aktor-aktor ideologi, namun berinisiatif mengidentifikasikan diri menjadi penganut ideologi setelah mempelajarinya dari literatur yang tersedia; (iii) fase pengaksian. Ideologi yang telah terpatri lalu mendorong individu-individu membentuk sebuah kekuatan kolektif berdasar pada kesamaan ideologi. Kemudian aksi dilakukan berlandaskan pada ajaran ideologi. Ideologi bukan cuma “mainan” akademisi, tetapi panduan aksi di medan artikulasi; (iv) fase rekonstruksi. Koreksi atau kritikan atas ideologi yang mengalami krisis mengharuskannya masuk ke dalam fase ini. Berbagai cacat-cacat ideologi terkuak dari berbagai kritikan; (v) fase reoperasi. Di sini ideologi yang sudah mendapatkan koreksi dan mengalami modifikasi dioperasikan.49 Kedua, media Islam. Media Islam adalah media yang menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai ideologi dalam kegiatan bermedia. Berita yang dihasilkan meliputi kegiatan dakwah, situasi negara-negara Muslim, tekanan-tekanan yang dihadapi umat Muslim di negara sendiri, pesan-pesan perdamaian yang dibawa Islam, ajaran agama, kisah para nabi, tafsir ayat dan kitab, hingga memuat artikel-artikel yang mendukung pertumbuhan pengetahuan warga mengenai Islam. 48 49 Bisma Yadhi Putra, “Jalan Neososialisme Chavez”, IndoPROGRESS, 3/5/2013. Ibid., Ketiga, media pragmatis. Media seperti ini banyak. Jika pun ada ideologi yang dianut, biasanya hanya berlaku pada waktu tertentu saja. Perubahan ideologi terjadi ketika ada tarikan yang berkisar soal rating atau profit yang bisa diperoleh. Media seperti ini bertiup ke mana saja angin keuntungan berembus. Selanjutnya, ketika media ini sedang menetap di satu ideologi, tingkat anutannya tidak dalam. Artinya, ideologi tidak dianut secara ketat. Apa yang menjadi klise kemudian adalah ketika dikategorikan ke dalam “media pragmatis”, awak medianya kemudian menyangkal bahwa ideologi media yang digunakan adalah demokrasi, sementara acap kali karena tarikan kepentingan yang ada media-media seperti ini memilih memublikasikan berita dengan bingkai yang menguntungkan elite, bukan pencerdasan masyarakat. Ini biasanya banyak diulas dalam kaitan antara media dengan kapitalisme. Cengkeraman kapitalisme atas media dapat dibaca dari banyak kasus dan hasil penelitian. Salah satunya pada bagaimana media pasca-Orde Baru membingkai pemberitaan mengenai isu “kebangkitan komunisme” atau “PKI sedang bangkit”, suatu framing pemberitaan yang tak bedanya dengan media-media di masa Orde Baru. Walaupun rezim Orde Baru saat ini sudah tumbang, sebagian besar media masih terbawa cara pandang khas ideologi Orde baru. Alih-alih menghadirkan wacana alternatif yang jernih mengenai isu komunisme, media justru menguatkan tafsir resmi yang selama puluhan tahun dipaksakan Orba, yakni dengan meneguhkan kembali gambaran komunisme yang anti-Tuhan, pembantai, pemberontak yang amat sadis dan barbar, tanpa menunjukkan usaha yang bersifat kritis dan dekonstruktif”.50 Apa yang ingin dicapai media dari pemberitaan seperti ini adalah rating berita, di mana media bisa membaca emosi sebagian besar orang terhadap PKI atau komunisme lalu memublikasikan teks-teks yang juga melanggengkan beberapa pengetahuan keliru mengenai hal tersebut. Semakin banyak pembaca, semakin memungkinkan pendapatan yang lebih besar bisa diraih. John Swinton, jurnalis senior di Amerika, dalam pidato pensiunnya menyampaikan pesan yang cukup keras kepada wartawan dan media yang menggemari manipulasi demi profit: “Kesibukan wartawan sekarang adalah menghancurkan kebenaran, sekaligus berbohong, untuk memutarbalikkan, untuk menjelek-jelekkan ... dan menjual dirinya untuk roti sehari-hari. Kita adalah alat, kapal bagi orang-orang kaya di belakang layar, H. Karomani, “Pengaruh Ideologi terhadap Wacana Berita dalam Media Massa”, Mediator, Vol. 5, No. 1, 2004. 50 kita adalah pendongkrak. Mereka menarik tali, kita menari. Bakat kita, kemampuan kita, dan hidup kita adalah milik orang-orang ini. Kita adalah pelacur intelektual”.51 Di era kebebasan pers, di mana kapitalisme begitu kuat cengkeramannya, Nafeez Mosaddeq Ahmed kemudian menulis pandangan tajamnya—untuk semakin menegaskan kritik Swinton: “Independensi media adalah sebuah mitos”.52 Akhirnya terjadilah pertempuran ideologi media. Media memang tidak saling serang, tetapi perlawanan terjadi di sektor wacana atau apa yang hendak media capai dari setiap pemberitaan. Wacana apa pun di media pada dasarnya merupakan suatu konstruksi yang bersifat ideologis. Kenyataannya memang memuat sejumlah kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pengusaha media cetak dan praktisi pers.53 Maka yang sudah pasti terjadi adalah bahwa “semua ideologi yang bertentangan secara mendasar dengan ideologi perusahaan (media) harus secara terlembaga diasumsikan tidak benar”.54 Sudah pasti di sini pengetahuan objektif akan susah diperoleh, terutama ketika mediamedia yang tidak memasukkan penjernihan fakta-fakta sebagai agendanya semakin kuat posisinya. Jadinya sama sekali tak keliru ketika filsuf Yasraf Amir Piliang berkata, “Ideologi selalu menciptakan pada diri setiap orang sebuah lukisan diri sebagai kebenaran, padahal semuanya adalah lukisan palsu yang diciptakan oleh para elite ideolog. Ilmu pengetahuan, sebaliknya, tidak pernah menciptakan kesadaran palsu seperti itu”.55 Sampai di sini, kita bisa melihat ada dua probabilitas posisi media ketika berhubungan dengan ideologi. Pertama, ideologi sebagai alat media. Kedua, media sebagai alat ideologi. Nafeez Mosaddeq Ahmed, “Why The Media Lies: The Corporate Structure of The Mass Media”, Media Monitors, 11/3/2002. 52 Ibid., 53 Umi Halwati, “Konstruksi Publikasi Nilai-nilai Ideologi dalam Pers (Media Massa)” Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 2, No. 1, 2014. 54 Nafeez Mosaddeq Ahmed, “Why The Media Lies...” Op.cit., 55 Yasraf Amir Piliang, 2012, Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna, Bandung: Pustaka Matahari, Hlm. 43. 51