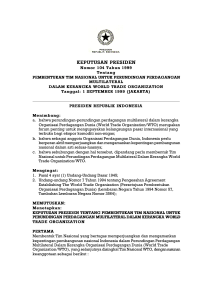BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perdagangan merupakan instrumen efektif untuk mendorong proses pembangunan. Beragam teori maupun kajian empiris menunjukan bahwa negara yang lebih terbuka terhadap pasar cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara yang protektif.1 Argumen ini semakin banyak diamini oleh banyak negara terutama paska berakhirnya perang dunia kedua, yang ditandai kemunculan kesadaran urgensi perdagangan lintas negara termasuk tata kelola yang menyertainya. Era tersebut sekaligus menjadi penanda mulai diinisiasinya pembentukan rezim perdagangan untuk memperkuat sistem perdagangan global agar berjalan lebih lancar dan bebas hambatan. Pada tahun 1948, 23 negara berkumpul dan berhasil menyepakati pembentukan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT). Kesepakatan ini sekaligus menjadi upaya awal menjadikan sistem perdagangan global yang lebih terbuka dan terkelola dengan baik. Harapannya, agar kesempatan tercapainya kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua negara yang ikut serta dalam skema perdagangan ini. Dalam perkembangannya, dimensi perdebatan mengenai perdagangan sendiri semakin meluas, tidak hanya hirau persoalan ekonomi melainkan juga politik. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya aktor yang terlibat baik dari negara maju maupun berkembang. Transformasi pelembagaan GATT dalam bentuk WTO Tulisan terkait korelasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi antara lain dapat dilacak dari karya Sachs & Warner (1995) yang meneliti kebijakan negara dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian mereka berhasil menunjukkan indeks yang memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi negara paska diambilnya kebijakan perdagangan terbuka memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. 1 1 (World Trade Organization) pada tahun 1995 semakin memperjelas pemposisian sekaligus pengkutuban antar kelompok negara ini. Kemiskinanan yang masih mewabah di negara berkembang terlebih di negara terbelakang/ LDC (Least Developed Country) menjadi persoalan yang memunculkan pertanyaan tentang klaim korelasi positif perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan. Bahkan, gagasan dari paham anti globalis memandang muram korelasi ini. Oleh mereka, alih-alih membawa kemakmuran, konsep perdagangan bebas yang terus dipromosikan WTO dianggap justru semakin menjerat dan menjerumuskan negara berkembang. Sementara pihak yang mendukung beranggapan, kemudahan akses pasar dan kepastian peraturan yang ditawarkan organisasi ini sulit untuk diabaikan begitu saja. Di tengah regangan perdebatan inilah negara berkembang semakin menyadari urgensi perjuangan politik dalam WTO sebagai rezim perdagangan utama dunia. Negara berkembang sendiri sebenarnya mendominasi keanggotaan WTO dengan presentase mencapai dua per tiga dari total anggota. Meski begitu, peran dan pemposisian mereka dalam perundingan yang dilakukan masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan ini diakibatkan oleh masih kurangnya kapasitas yang berkelindan dengan berbagai persoalan struktural yang dimiliki. Terlebih prinsip transparansi dan non diskriminasi yang menjadi pilar dalam sistem WTO sendiri sering disalahpahami dan disalahgunakan sebagai dalih negara maju untuk melanggengkan status quo untuk konsesi yang lebih menguntungkan mereka. Negara berkembang memang tidak tinggal diam begitu saja, namun tarik ulur kepentingan yang terjadi malah berimbas pada ketidakjelasan dan lambannya keputusan perundingan. Jika hal ini tidak segera dijembatani, bukan tidak mungkin yang terjadi malah pelemahan sistem perdagangan multilateral dan peminggiran kepentingan negara berkembang itu 2 sendiri. Keberadaan sistem perdagangan global yang menjadi cita-cita bisa saja sekedar jargon yang tidak berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan negara berkembang. Reposisi negara berkembang menjadi misi yang sangat penting dalam mengupayakan tercapainya rasa keadilan (sense of fairness) yang lebih baik dalam tubuh WTO. Persoalan keadilan ini sendiri merupakan salah satu isu utama baik dalam konteks perdagangan maupun ranah ekonomi politik internasional yang lebih luas. Namun dalam praksisnya, keadilan disini cenderung berada dalam domain politik sehingga sifatnya lebih prosedural ketimbang substantif. Turunan prinsip non diskriminasi WTO —Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment (NT)— menjadi bentuk nyata dari argumen ini. Secara teori, kedua prinsip ini merupakan bentuk keadilan karena setiap negara akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pembedaan. Namun jika ditinjau lebih jauh, perlakuan yang sama ini—jika diberlakukan tanpa mempertimbangkan status dan kemampuan ekonomi negara bersangkutan— bias jadi hanya akan menempatkan negara tersebut dalam posisi yang dirugikan. Upaya pemajuan kepentingan negara berkembang di WTO diperlukan guna memperbaiki pemposisian negara berkembang agar kedepannya peran yang dimainkan serta manfaat yang diraih menjadi lebih baik. Terlebih jika dibandingkan dengan institusi ekonomi dunia lain seperti IMF dan Bank Dunia, kesempatan yang ditawarkan mekanisme pengambilan keputusan WTO bagi negara berkembang jauh lebih memungkinkan. Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh kedua institusi sebelumnya sangat didominasi oleh pengaruh lembaga tertentu dimana penentuan mengenai putusan yang harus diambil sangat dipengaruhi saham yang disumbang negara anggota. Hak suara yang dimiliki negara anggota sangat timpang sehingga persoalan akuntabilitas keputusan terlebih yang mewakili kepentingan negara berkembang sulit terwadahi. Di IMF misalnya, saham negara maju 3 secara keseluruhan mencapai 60,45 persen yang didominasi AS dengan 17,29 persen, sementara negara berkembang hanya mencapai 30,32 persen.2 Hal yang hampir mirip terjadi dengan Bank Dunia karena hak suara organisasi ini juga dipengaruhi oleh suara pokok (basic votes) yang dimiliki di IMF.3 Tradisi kedua institusi ini dapat dipastikan menjadi milik negara maju, dengan negara dengan modal lebih banyak akan memiliki hak suara lebih besar. Pengalaman hingga saat ini, IMF sangat dipengaruhi oleh negara-negara Eropa sementara Bank Dunia berada dibawah pengaruh kuat Amerika Serikat.4 Hal ini sangat berbeda dalam mekanisme WTO dimana negara anggotanya memiliki hak suara yang sama. Secara teori, keberadaan sistem demokratis yang transparan, inklusif, serta berbasis konsesus jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kepentingan negara berkembang. Analisa kuasa (power) diperlukan karena di dalam sistem demokratis selalu berkelindan mekanisme kuasa didalamnya. Kuasa dalam berbagai modenya selalu mengambil peranan dalam persoalan, menurut Harold Laswell (1936), siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Imbasnya, keberadaan kuasa yang dimiliki masing-masing aktor tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam setiap upaya analisa mengenai WTO. Pemahaman mengenai aspek kuasa ini penting untuk memahami relasi yang terbangun antara negara maju dan berkembang. Kuasa negara maju baik secara politis maupun teknis lebih kuat dibandingkan negara berkembang karena didukung kapasitas yang lebih baik. Disparitas kuasa yang dimiliki antara keduanya memunculkan tantangan tersendiri terutama bagi negara Bahagijo, S. (ed) (2006). Globalisasi Menghempas Indonesia. Jakarta: LP3ES hal. 11 Suprijanto, A. ‗Melihat dari Jakarta‘, dalam Bahagijo, S. (ed) (2006), hal. 301 4 Harinowo, C. (2004). IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. Jakarta: Gramedia, hal. 89 2 3 4 berkembang dalam memperjuangkan kepentingannya.5 Analisa berbasis kuasa ini bermanfaat untuk pemetaan yang lebih mendalam untuk memahami proses perundingan yang dijalani, termasuk dalam pencapaian Paket Bali dalam perundingan KTM IX WTO. Paket Bali sendiri merupakan sebagian dari total isu runding perundingan Putaran Doha (Doha Development Agenda/ DAA) yang mencakup isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan paket pembangunan LDC. Mengingat pengalaman kegagalan pencapaian dalam empat perundingan KTM sebelumnya, tentu ada konteks serta faktor yang berbeda dengan yang ada pada KTM IX tersebut. Tulisan ini beranggapan, keberhasilan ini terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan karakter serta identitas WTO mengenai relasi kuasa antara negara maju dan berkembang. Hal ini bisa dikenali dalam konteks konstelasi kuasa paska krisis yang memberikan dampak serius pada negara maju. Hal ini menyebabkan, konsesi yang mereka inginkan melalui koalisi di WTO bergeser untuk lebih mengadopsi kepentingan negara berkembang. Sementara di sisi lain, keberadaan negara berkembang terutama advanced developing countries/ emerging countries yang lebih resilien terhadap krisis semakin memperkuat koalisi dan tuntutan konsesi negara berkembang. Anggapan ini didukung data yang dikeluarkan International Comparison Program (ICP) yang menunjukkan bahwa total produksi barang dan jasa global pada 2011 senilai 90 trilliun dollar, hampir setengahnya berasal dari negara berkembang.6 Sumber yang sama menyebutkan pada tahun tersebut, GDP (gross domestic product) dari enam negara berkembang China, India, Russia, Brasil, Indonesia, dan Meksiko senilai 32.3 persen, hampir menyamai GDP dari enam negara Gerhart, P. M. & Kella A.S. (2004). Power and Preferences: Develop ing Countries and the Role of the WTO Appellate Body dalam North Carolina Journal Of International Law & Commercial [vol.30], hal.515 6 World Bank, 2011 International Comparison Program Summary Results Release Compares the Real Size of the World Economies dapat diakses di http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/29/2011-internationalcomparison-program-results-compare-real-size-world-economies, [ 17 Januari 2014] 5 5 maju AS, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Analisa faktorfaktor di atas dibutuhkan untuk mengenali pertanda dari adanya pergeseran pemposisian dalam konstelasi kuasa geo-ekopolitik global dan pengaruhnya dalam kekuatan koalisi di WTO. Pelemahan kapasitas ekonomi terutama negara maju akibat krisis global sejak akhir 2007 ikut mendorong pergeseran ini sekaligus mempengaruhi wacana (discourse) serta pembicaraan dalam perundingan WTO. Statemen dari UNCTAD mengungkapkan jika krisis global dan tidak meratanya recovery perdagangan memperkuat terjadinya pergeseran menuju keseimbangan kekuatan ekonomi dunia yang ditandai relatif menurunnya kekuatan negara maju dan kebangkitan negara berkembang.7 Krisis ini sendiri sebenarnya disebabkan oleh praktek over liberalisasi di sektor jasa keuangan dan investasi. Namun solusi pragmatis dari negara yang terkena krisis dengan memunculkan kebijakan proteksionis keberlangsungan dan perdagangan nasionalis ekstrim, multilateral. Contoh mengancam kebijakan- kebijakan ini antara lain AS yang memunculkan kembali gagasan neokeynesian dengan kebijakan Buy America Act, negara Mercosur (Amerika latin) dengan kebijakan safeguard atau proteksi industri lokal dengan bea masuk, serta di Singapura, Malaysia, dan Turki yang mengeluarkan kebijakan proteksi tenaga kerja dengan resillence package. Proteksionisme yang berkelindan dengan maraknya perjanjian perdagangan bilateral maupun kemunculan regionalisme seperti TPP (Trans Pasific Partnership) menjadi tantangan serius bagi perdagangan multilateral di bawah kerangka WTO. Pelaksanaan KTM IX Bali menjadi momentum yang tepat guna merefleksikan kembali keberlanjutan perdagangan multilateral yang selama ini stagnan pada deadlock perundingan Putaran Doha, sekaligus mengupayakan cara Globalization And The Shifting Balance In The World Economy dapat diakses di http://dgff.unctad.org/chapter1/1.html, [ 17 Januari 2014] 7 6 yang lebih baik untuk memenuhi rasa keadilan bagi negara berkembang. Perspektif Indonesia Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ministerial Conference ke-9 WTO pada 3-6 Desember 2013 di Bali. Pertemuan ini sendiri merupakan momentum bagi keberlanjutan perundingan Putaran Doha yang mulai digelar pada KTM IV di Doha, Qatar, dua belas tahun sebelumnya. Putaran ini selain menjadi peluang penegakan sense of fairness bagi negara berkembang karena substansi isu runding yang sebagian besar merupakan domain mereka, juga menghadirkan peluang bagi keberlanjutan peta jalan perundingan Putaran Doha setelahnya. Kesempatan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian kapasitas negara berkembang mengingat rekam sejarah perundingan-perundingan WTO terdahulu termasuk ketika masih bernama GATT yang sangat sedikit mengakomodasi kepentingan nereka. Dari perspektif Indonesia, KTM IX Bali menjadi ajang pembuktian bagi pelaksanaan dan strategi diplomasi ekonomi yang dimiliki. Kebutuhan akan diplomasi ekonomi ini sendiri semakin meningkat paska reformasi yang berperan untuk memperkuat perekonomian sekaligus menjawab tantangan dari semakin meluasnya globalisasi. Pelaksanaannya yang efektif diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendapat manfaat riil seperti investasi asing, pengembangan infrastruktur, transfer teknologi, maupun akses pasar perdagangan di negara non tradisional. Semakin membaiknya perekonomian Indonesia memperkuat kapasitas, daya tawar, dan sekaligus peluang untuk menjadi pemain kunci dan jembatan penghubung antara negara berkembang dengan negara maju. Indonesia berpeluang sebagai garda depan negara berkembang dalam perundingan-perundingan WTO. Dalam konteks 7 KTM IX Bali, peluang ini hadir dengan kepememimpinannya memajukan kepentingan negara berkembang dalam institusi ini. Sebelum KTM IX Bali, Indonesia sebenarnya telah cukup memiliki pengalaman dalam hal ini. Peluncuran Perundingan Doha merupakan contoh keberhasilan bagi pelaksanaan diplomasi ekonomi sekaligus peluang memperbesar kesempatan bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk lebih bersatu dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.8 Inisiatif Indonesia mengkoordinir 32 negara lain dalam perundingan KTM V WTO di Cancun, Meksiko, yang berhasil membentuk kelompok kepentingan G-33 menjadi pembuktian lain. Kepemimpinan dalam koalisi negara berkembang untuk isu pertanian ini membuka jalan kepemimpinan lain di luar isu pertanian seperti akses pasar produk industri, jasa, perdagangan, lingkungan hidup, dan fasilitasi perdagangan. Dengan koordinasi negara berkembang yang semakin baik, diharapkan kekuatan jejaring dan koalisi yang dibutuhkan untuk berunding dalam forum WTO juga semakin menguat. Hasilnya, meskipun penutupan KTM IX Bali sempat tertunda sehari, pertemuan tersebut akhirnya berhasil meloloskan Paket Bali sebagai putusan perundingan. Pentingnya pencapaian ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo yang mengklaim sebagai progress paling penting dalam perdagangan multilateral sejak organisasi ini didirikan pada 1994.9 Peluang dan potensi nilai perdagangan dunia dari implementasi Paket Bali dikatakan diperkirakan mencapai 980 miliar dollar AS yang akan membuka Nasir dalam Cahyono (2008). Menjinakkan Meta Kuasa Global. Jakarta: LP3ES hal.179 Wto Bali Deal Offers More Symbolism Than Substance dapat diakses di http://theconversation.com/wto-bali-deal-offers-more-symbolism-than-substance21292, [17 Januari 2014] 8 9 8 lapangan pekerjaan sejumlah 21 juta dengan 18 juta diantaranya berada di negara berkembang.10 Mengapa baru di Bali perundingan Doha bisa menghasilkan keputusan? Apa alasan dibalik keberhasilan tersebut? Apa konteks yang membedakan perundingan KTM IX Bali dengan KTM-KTM sebelumnya? Bagaimana peranan Indonesia didalamnya? Dengan menggunakan pendekatan kuasa (power) dari Bernett-Duvall dan strategi integrative-distributive dari Odell, penelitian ini akan berupaya untuk memahami alasan dibalik pencapaian tersebut dengan melacak alur progress modalitas isu runding terutama menjelang perundingan berlangsung serta peranan aktor-aktor terkait, termasuk Indonesia. B. Pokok Permasalahan Dari latar belakang sebelumnya, didapat elaborasi lokus persoalan sebagai berikut: Mengapa baru pada perundingan KTM IX WTO Bali perundingan Putaran Doha bisa menghasilkan keputusan? Bagaimana peran dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam pencapaian tersebut? C. Tinjauan Pustaka Bagian ini akan meninjau beberapa literalur terkait dengan fokus kajian pemajuan kepentingan negara berkembang dalam perundingan WTO. Dengan beberapa konteks yang berbeda, terdapat beberapa literatur sebelumnya yang membahas persoalan pemajuan kepentingan ini. Literatur ini cukup berguna untuk memberikan pemahaman Hufbauer & Schott (2013), Pay off from the World Trade Agenda 2013 dapat diakses dari http://www.iie.com/publications/papers/hufbauerschott20130422.pdf, [5 Februari 2014] 10 9 mengenai posisi negara berkembang di WTO untuk dielaborsi lebih jauh dalam konteks pelaksanaan KTM IX. Pemposisian serta upaya pemajuan kepentingan negara berkembang memang merupakan persoalan yang kompleks ditinjau dari perspektif negara berkembang. Dilema terkadang muncul disini, namun kesempatan yang disediakan oleh sebuah rezim internasional tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk itu, negara berkembang harus menyikapinya dengan cerdas agar kesempatan yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Pilihan untuk memanfaatkan kesempatan sekecil apapun dalam forum perundingan WTO nampaknya lebih rasional dan bijaksana ditengah ruang kebijakan alternatif lain yang masih sangat kecil. Jagdihs Bhagwati dalam In Defense of Globalization (2004) mengingatkan bahwa dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan interkonektivitas, upaya paling penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan manfaat dari globalisasi yang sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa perdagangan memang tidak selalu menghilangkan membawa pada penghalang pertumbuhan, domestik yang namun ada maka dengan negara berkembang kemungkinan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. WTO merupakan tempat yang kompleks sebagai sarana memperjuangkan kepentingan, namun jika dikelola dengan baik hasil yang didapat oleh negara berkembang akan bisa maksimal. Studi yang dilakukan oleh Michalopoulos yang berjudul The Participation of Developing Countries in WTO (1997) menjadi karya penting untuk memahami keterlibatan negara berkembang dalam negosiasi di WTO. Penelitian ini menunjukkan beberapa isu utama yang menjadi perhatian bagi negara berkembang. Pertama, isu representasi. Hal ini terkait ukuran jumlah dan kapasitas perwakilan dalam setiap misi di WTO. Kedua, isu keketuaan (chairmanship). Hal ini terkait alokasi jumlah negara berkembang yang mendapatkan jatah pimpinan di dewan maupun badan WTO. Ketiga, isu kapasitas 10 institusional. Hal ini terkait efektifitas dalam partisipasi dan representasi. Ia menjelaskan, dalam kerangka teknis, banyak perwakilan misi negara berkembang di Jenewa tidak memadai. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan negara maju yang memiliki perwakilan misi yang sangat besar.11 Representasi yang dihasilkan dari banyaknya negara berkembang yang melakukan aksesi ke WTO paska putaran Uruguay tidak diimbangi partisipasi konsisten untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kapasitas dan staffing dari banyak negara berkembang tidak sepadan dengan kompleksitas isu dan jumlah pertemuan yang dilaksanakan di WTO. Menanggapi permasalahan ini, Michalopoulos menyarankan kepada negara berkembang yang menghadapi persoalan ini untuk meningkatkan efektivitas strategi seperti memastikan arus informasi dapat berjalan dengan baik, identifikasi negara yang memiliki kepentingan mirip namun memiliki partisipasi yang lebih baik, penguatan kapasitas domestik, dan mendukung aksesi negara lain yang sekiranya dapat memperkuat perjuangan kepentingannya.12 Penelitian ini menekankan pada aspek pentingnya strategi dan koalisi. Dalam KTM IX Bali, identifikasi kepentingan masing-masing negara menjadi bagian integral dalam menyusun strategi perundingan sekaligus mengkerucutkan pemposisian dari masing-masing koalisi negara. Tulisan lain yang hampir sama dari Kishan S. Rana dalam Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries dalam buku Bayne dan Wollcock berjudul The New Economic Diplomacy (2007: 201-220) mempertegas gambaran mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang. Perbedaan diplomasi ekonomi negara berkembang merefleksikan perbedaan respon masingmasing negara terhadap persoalan lingkungan eksternal. Persoalan Michalopoulos (1997). The Participation of The Developing Countries in The WTO dapat diakses di http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-1906, [12 Januri 2014] 12 Michalopoulos (1997), hal: 27-28 11 11 yang muncul kadang tidak ditanggapi dengan serius sebagai akibat lemahnya diplomasi baik dalam ranah ekonomi maupun politik. Kelemahan yang mereka miliki tidak dicoba untuk disiasati dengan penguatan jejaring dengan negara lain yang relevan. Selain itu, korelasi kebijakan ekonomi domestik dengan diplomasi ekonomi harus sejalan. Peningkatan kapasitas domestik sangat berpengaruh pada penguatan kekuatan negara tersebut di luar negeri. Kombinasi antara politik luar negeri dengan perdagangan luar negeri juga merupakan merupakan prinsip yang penting. Sementara dari segi yang lebih teknis, diperlukan penguatan skill untuk penguatan jejaring aktor diplomasi. Terakhir, proses pembelajaran dari praktek yang dialami negara lain penting untuk perbaikan manajemen sistem ekonomi untuk diplomasi di era globalisasi. Kelemahan yang dimiliki oleh negara berkembang bukan berarti mereka menjadi tidak berdaya dalam perundingan. Sheila Page dalam Developing Countries in GATT/WTO Negotiations (2002) menilai bahwa hasil dari negosiasi internasional bukan sekedar ditentukan oleh kuasa relatif dari masing-masing aktor, namun ada potensi dari aliansi antar negara untuk representasi dan mobilisasi kepentingan. Ia menambahkan, bagaimana struktur dan institusi formal dari kesepakatan menyediakan basis analisis pada dasar sistemik mengenai bagaimana negosiasi internasional dapat mempengaruhi kepentingan nasional. Hal ini dikatakan dapat meningkatkan kualitas partisipasi dan kesuksesan negosiasi. Jika negosiasi berhasil maka akan memunculkan efisiensi baik bagi pelaku bisnis maupun negara yang akhirnya akan menghilangkan rintangan dagang dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Masih menurut Page, selalu ada kepentingan yang sama dalam sebuah negosiasi untuk tata kelola perdagangan. Dalam konteks KTM IX Bali, hal ini dapat dilacak pada kemunculan konsesus untuk menjadikan sentralitas institusi WTO dan perdagangan multilateral sebagai bagian dari recovery krisis. Hal lain 12 yang dipertegas oleh Page adalah bahwa salah satu elemen dari negosiasi internasional di WTO adalah negara tidak lagi terlalu berperan sebagai unit yang berdaulat.13 Hal ini berimplikasi pada analisa kuasa yang digunakan tidak bisa lagi menggunakan perspektif tunggal (ukuran ekonomi negara, kemampuan finansial, atau bahkan kekuatan militer) karena tidak relevan lagi.14 Bargaining dan pertukaran konsesi antar negara termasuk negara kuat dan lemah sangat memungkinkan karena alur perundingan yang biasanya dilaksanakan bertahap. Namun hal ini tetap kembali pada bagaimana negara terkait mengelola kepentingan, kuasa, dan koalisi mereka. Penelitian lain yang dilakukan Olajumoke Oduwole berjudul Realigning International Trade Negotiation Asymmetry: Developing Country Coalition Strategy in The WTO Doha Round Agriculture Negotiations (2011) memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi diplomasi ekonomi negara berkembang di WTO. Meskipun secara spesifik penelitian yang ia lakukan terkait sektor pertanian, namun tetap bisa memberikan gambaran hal serupa di sektor-sektor lain. Ia menggambarkan bagaimana kontestasi negara berkembang yang lemah dalam forum WTO yang diakibatkan oleh bargaining power yang terbatas yang berimplikasi pada banyak hasil perundingan yang dilakukan serta sistem internasional pada umumnya. Melihat realita tersebut, dibutuhkan adanya strategi komprehensif dalam hal pengelompokan (clustering) isu, penggelolaan sumber daya yang dimiliki, serta pembentukan aliansi untuk memperkuat pemposisian dan bargaining mereka. Penelitian ini menganalisa pergeseran yang terjadi pada kekuatan negara berkembang khususnya pada isu pertanian putaran Doha. Ia melihat koalisi empat kelompok utama: Cotton-4, G-20, G-33, dan G-99 sebagai contoh menarik bagaimana strategi koalisi dijalankan. Ia membandingkan dan mengkontraskan Page, Sheila (2002). Developing Countries in GATT/WTO Negotiations (kertas kerja). London: Overseas Development Institute, hal.9 14 Page (2002), hal.10 13 13 strategi dari masing-masing koalisi selama negosiasi berlangsung. Hasilnya, strategi pertukaran konsesi yang dilakukan oleh masingmasing koalisi sangat efektif dalam memperkuat leverage isu pertanian dalam WTO.15 Penelitian ini mengapresiasi positif upaya negara berkembang ini karena hasilnya, modalitas yang dihasilkan dari perundingan pertanian putaran Doha pada modalitas terakhir tahun 2008 relatif lebih menguntungkan negara berkembang dibandingkan saat awal Putaran Doha terlebih pada saat Putaran Uruguay. Penelitian ini akan mencoba melihat progress modalitas yang sama pada dua isu lain yang dibahas pada KTM IX Bali: Paket Pembangunan LDC dan Fasilitasi Perdagangan. Upaya penyelesaian perundingan Putaran Doha sendiri merupakan persoalan yang cukup kompleks dan pelik. Paul Collier menulis dalam Why The Wto Is Deadlocked: And What Can Be Done About It (2005), setidaknya terdapat tiga persoalan mengapa perundingan ini berjalan begitu rumit. Pertama, terdapat perbedaan mendasar antar anggota WTO sehingga jika dilakukan pertukaran konsesi yang terjadi bisa jadi akan merugikan salah satu pihak. Negara berkembang menginginkan konsesi berupa ‗transfer‘ agar ada manfaat langsung yang mereka dapatkan. Contoh dari ‗transfer‘ ini seperti bantuan teknis atau perlakuan khusus dan berbeda. Kedua, terdapat kelompok negara –terutama negara berkembang— di WTO yang menganggap bahwa mereka telah cukup termarjinalisasi dari perekonomian dunia sehingga tidak memiliki dasar bargaining untuk kepentingan bersama. Padahal, sistem konsesus yang dianut mengharuskan semua negara untuk menyepakati perundingan yang disepakati. Dan ketiga, meskipun terdapat negara berkembang yang masih memiliki bargaining dalam forum perundingan, namun tetap saja sulit untuk mencapai kesepakatan seperti pada era GATT karena Oduwole, Olajumoke O. (2011), Negotiation Asymmetry: Developing Country Coalition Strategy in the.WTO Doha Round Agriculture Negotiations (disertasi). Stanford University, hal. 211 15 14 kesepakatan yang diputuskan terlalu lintas sektoral sehingga jika ditransformasi dalam aturan domestik negara membutuhkan adaptasi yang banyak dari beragam aturan yang telah ada. Persoalan-persoalan ini belum ditambah faktor negara free rider yang bisa saja membuyarkan strategi serta peta koalisi yang ada. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah-masalah ini, Collier mengusulkan beberapa alternatif. Pertama, menyelesaikan tegangan yang ada antara bargaining dan transfer. Artinya, jika dilihat secara obyektif, fungsi dari perundingan di WTO adalah tawar menawar konsesi bukan seperti saat ini dimana yang terjadi adalah beban pada perundingan yang terlalu besar. Mekanisme ‗transfer‘ yang memungkinkan —untuk misalnya penerapan perlakuan khusus dan berbeda— dikembalikan pada sekretariat WTO. Kedua, menyelesaikan tegangan antara penerapan aturan dan kedaulatan negara. Sebagaimana kesepakatan plurilateral lain, permasalahan ini muncul karena semua negara anggota tanpa terkecuali harus menerapkan aturan meskipun isu yang disepakati belum tentu merupakan domain dan bagian dari kepentingan mereka. Untuk itu ia mengusulkan bahwa harus ada mekanisme tertentu yang memberikan fleksibilitas pada aspek ini. Ketiga, memberikan preferensi tertentu kepada negara LDC agar mendapatkan hasil yang lebih besar dari WTO. Keempat, memfasilitasi kesepakatan anatar OECD dan koalisi negara berkembang. Hal ini disebabkan kelompok negara berkembang menjadi kunci perundingan dalam proses-proses perundingan terakhir. Fasilitasi ini bisa dilakukan dengan memperjelas konsesi pada persoalan kompensasi yang diperoleh negara berkembang yang selama ini menjadi salah satu isu pokok perdebatan. Kelima, memfasilitasi liberalisasi intra negara berkembang. Hal ini dikarenakan hambatan perdagangan intra negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju sehingga fasilitasi melalui mekanisme regional diharapkan bisa membuka jalan bagi keberhasilan di tingkat 15 multilateral. Lebih jauh, hal ini bisa juga dilakukan dengan evaluasi terhadap konsep MFN untuk memberikan keleluasaan pembedaan pada negara tertentu. Keenam, dari sisi institusi WTO sendiri dibutuhkan penguatan pada aspek fasilitasi pasar dan kelembagaan sekretariat. Usulan dari Coller ini cukup berkorelasi dengan proses perundingan KTM IX Bali. Dilihat dari aspek tema perundingan, maka tiga isu runding yang dibahas: pertanian, fasilitasi perdagangan, dan LDC sangat mewakili aspirasi kepentingan dari masing-masing kelompok koalisi negara. D. Landasan Analisa Untuk mengeksplorasi lebih jauh lokus persoalan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuasa (power) dari Barnett dan Duvall serta strategi integrative-distributive dari Odell sebagai landasan analisa. Mode Kuasa Barnett dan Duvall Terkait dengan relasi kuasa dengan diplomasi ekonomi, Odell menjelaskan bahwa hasil dari negosiasi ekonomi politik juga dipengaruhi oleh faktor lain selain proses negosiasi seperi perubahan teknologi, tren pasar, peraturan internasional, institusi domestik, dan struktur kuasa.16 Menurut Jessop, faktor perubahan kuasa penting untuk mengenali perubahan pada tata kelola yang ada. 17 Kuasa dalam berbagai mode dan relasinya menjadi bagian penting dalam tata kelola yang terbentuk.Karakter negosiasi di WTO yang cenderung inklusif dengan satu negara satu suara menghendaki adanya blok-blok negara dengan negosiasi kepentingan antara mereka. Meskipun lembaga antar pemerintah ini merepresentasikan keanggotaannya secara suka rela, Odell (2006), How to Negotiate Over Trade:a Summaryof New Research for Developing(kertas kerja). Jenewa: Geneva International Academic Network (GIAN) hal.18 17 Griffin (2000), Why Geography matters in Theory of Governance, dalam Political Studies Review volume 10 2012 16 16 pluralis, dan berorientasi kerjasama, kenyataannya negara yang lebih lemah yang dijadikan sebagai objek dalam isu-isu yang lebih luas yang mencakup ranah sosial, ekonomi, dan politik.18 Pertukaran konsesi menjadi sangat ketat yang tentunya membutuhkan kejelian strategi dari koalisi-koalisi yang terbentuk. Menghadapi kenyataan ini, aktoraktor yang bermain harus jeli melihat peluang dengan menggunakan strategi yang tepat. Meskipun kuasa (power) sendiri merupakan salah satu konsep dasar ekonomi politik, hingga kini tidak terdapat kesepakatan definitif tentangnya. Pemahaman sederhana mengenai konsep ini adalah kemampuan satu pihak untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan dari pihak lain. Giddens (1989) menjelaskan konsep ini sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan kepentingannya meskipun mendapatkan perlawanan dari pihak lain, dengan kadang melibatkan penggunaan kekuatan langsung atau disertai dengan penggunaan gagasan (ideologi) yang mendasari tindakan dari pihak yang lebih kuat.19 Dalam rezim ekonomi internasional, dimensi politik memainkan peranannya dalam persoalan kuasa terutama dalam hal siapa memutuskan apa. Pemahaman yang utuh tentang permainan kuasa ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku ataupun konstelasi aktor yang bermain, yang akhirnya akan memberikan masukan tepat bagi langkah strategis yang akan diambil aktor tersebut. Gagasan dari Gramsci dan Neogramscian memberikan perhatian dan penekanan pada faktor susunan ide, pengetahuan, dan pelembagaannya yang mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Sementara Barnett dan Duvall (2005) menjabarkan lebih jauh dan kompleks mengenai bagaimana kuasa bekerja. Bagi mereka, kuasa bekerja dengan berbagai bentuk dan ekspresi yang tidak bisa diungkap begitu saja dengan formula Bernett, Michael & Raymond Duvall (2005), Power in Global Governance, New York: Cambridge University Press, hal. 49 19Giddens, Anthony. (1989), Sociology. London: Cambridge, hal: 52 18 17 tunggal.20 Kuasa merupakan pembentukan dari serangkaian akibat kepada para pelaku di dalam dan selama proses hubungan sosial, yang membentuk kapasitas mereka untuk menentukan takdirnya.21 Mekanisme kuasa disini sendiri dapat dilihat dari macam hubungan sosial yang mempengaruhi maupun berimbas pada kapasitas para pelaku serta dari spesifikasi dari hubungan sosial apakah ‗langsung‘ atau ‗tersebar‘. Dalam konteks yang hubungan sosial, kuasa di sini berada dalam relasi sosial yang ada dan melembaga dalam tatanan sosial yang terbentuk dari relasi sosial tersebut. Hubungan sosial ini membentuk siapa yang menjadi pelaku serta praktek dan kapasitas yang dilaksanakan oleh pelaku tersebut. Sementara dalam konteks hubungan sosial, pola ‗langsung‘ dapat dipahami sebagai interaksi penggunaan kekuasaan tanpa melalui perantara sementara ‗menyebar‘ dapat dipahami sebagai pendistribusian kekuasaan melalui perantara ‗tidak langsung‘. Mereka kemudian menjabarkan kuasa ini dalam empat dimensi melalui compulsory power, institutional power, structural power, dan productive power. Compulsory power merupakan bentuk paling tradisional yang menggambarkan relasi aktor mengendalikan lainnya. Negara yang lebih kuat secara langsung menggunakan sumber kuasa mereka untuk menekan tindakan negara yang lebih lemah agar sesuai keinginan mereka.22 Institutional power merupakan bentuk kuasa dimana satu pihak mengendalikan secara tidak langsung pihak lainnya melalui institusi dengan beragam peraturan, prosedur, atau kesepakatan yang dimiliki institusi tersebut. Hal ini berlangsung baik dalam bentuk institusi langsung maupun tidak langsung.23 Structural power digambarkan sebagai relasi struktural baik politik maupun ekonomi menundukan kapasitas sosial dan pihak-pihak Bernett & Duvall (2005), hal. 2 Barnett & Duval (2005). Power in international Politics, dalam International Organization, Vol. 59, No. 1, Winter 2005, hal. 39-75 22 Bernett & Duvall (2005), hal. 14 23 Barnett & Duval (2005). Power in international Politics, hal.51 20 21 18 berkepentingan. Konsep ini hirau terhadap pelembagaan dari relasi sosial dalam konteks sosial (struktur) yang mendefinisikan identitas dimana aktor terlibat, yang menurut pandangan ini meliputi kapasitas relasi sosial, subjektivitas, dan kepentingan aktor yang dibentuk oleh posisi sosial kemiripannya yang dimiliki.24 dengan Bernett institutional dan power Duvall menyadari sehingga untuk membedakannya mereka memperjelas bahwa institutional power hirau pada pembatasan tindakan tertentu sementara structural power hirau pada penetapan kapasitas sosial dalam hubungannya pada pemajuan kepentingan.25 Untuk sederhananya, mereka membandingkan dengan konsep klasik struktural hubungan antara pemilik modal dan kelas pekerja sebagai konsekuensi keberadaan model produksi kapitalis global26 dan konsep dalam teori sistem dunia yang menggambarkan fundamental struktur kelas negara.27 Sementara productive power merupakan bentuk kuasa dalam kaitannya dengan produksi makna, wacana, dan pengetahuan dalam sistem sosial yang mendukung untuk dilaksanakanya pemajuan kepentingan tertentu. Productive power bukan lagi dikuasai oleh aktor tertentu namun bekerja melalui makna yang dihasilkan dari tindakan aktor.28 Penjabaran lebih lanjut tergambar dalam matriks berikut: Matriks 1: Ragam Kuasa Relational specificity Direct Diffuse Compulsory Institusional Power Interactions of works specific actors through Social Relations Structural of constitution Productive Sumber: Types of power29 Barnett & Duvall (2005), hal.18 Barnett & Duvall (2005). Power in international Politics, hal.53 26 Barnett & Duvall (2005), hal.3 27 Barnett & Duvall (2005). Power in international Politics, hal.54 28 Barnett & Duvall (2005). Power in international Politics, hal.55 29 Bernett & Duval (2005), hal: 12 24 25 19 Perkembangan pemikiran telah menghantarkan spektrum kuasa dalam banyak ranah dari hal yang sifatnya terukur (tangible) seperti kekuatan militer atau ekonomi hingga yang (intangible) seperti gagasan dan wacana (discourse). Empat hal yang tersebut dalam tabel diatas memperlihatkan bentuk kuasa dalam mode yang berbeda. Penggunaan empat tipe kuasa dari langgam perspektif yang berbeda ini tentu saja bukan dimaksudkan untuk bersikap eklektik melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kuasa yang ada. Penelitian ini berpendapat, penggunaan keempat mode tersebut sangat relevan karena sifatnya yang saling mendukung dalam pelembagaan sebuah kuasa. Namun untuk compulsory power tidak akan terlalu banyak digunakan dengan asumsi mekanisme koalisi dalam model pengambilan keputusan WTO relatif dapat meredamnya. Adapun operasionalisasi dari penjabaran di atas tergambar dalam matriks berikut: Matriks 2: Operasionalisasi Kuasa 20 Analisa kuasa ini bisa dilacak pada progress baik teks isu runding maupun kekuatan koalisi negara sebagai modalitas dalam pencapaian paket Bali. Secara sederhana, modalitas sendiri adalah atribut atau keadaan yang menandakan sikap tertentu.30 Sementara menurut Giddens (1984) —yang menggunakan istilah ini dalam teori strukturasinya— mendefinisikan konsep ini sebagai sarana atau instrumen yang membuat interaksi memungkinkan. Ia cukup komprehensif dalam mengartikulasikan modalitas ini yakni sebagai skema interpretatif, fasilitas, dan norma.31 Dalam konteks diplomasi, modalitas di sini bisa dipahami sebagai serangkaian petunjuk, formula, target, maupun spesifik aturan yang memungkinkan untuk dicapainya tujuan dalam negosiasi. Telah terjadi perubahan dan disposisi kuasa yang signifikan dalam WTO terutama paska pelaksanaan putaran Doha dalam konteks pemajuan kepentingan negara berkembang. Saat ini, sebagian besar negara berkembang menjadi anggota dalam forum ini. Spektrum dunia yang sebelumnya sangat dikuasai oleh negara maju mulai memendar dengan kemunculan emerging power yang antara lain diwakili kehadiran negara berkembang di G-2032 dan BRIC. Modalitas dari koalisi negara berkembang paska perundingan Doha semakin menguat dengan berbagai isu yang menjadi spesifikasinya. Modality dapat diakses di http://dictionary.reference.com/browse/modality, [21 Januari 2014] 31 Gidden, Anthony (1984). The Constitution of Society diterjemahkan oleh Maufur & Daryanto (2010). Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat (terj). Yogyakarta Pustaka Pelajar, hal: 46 32 G-20 yang dimaksud disini berbeda dengan koalisi G-20 pertanian dalam konteks koalisi di WTO. istilah G-20 yang terakhir ini yang akan banyak digunakan dalam pembahasan penelitian ini. 30 21 Strategi Integrative-Distributive Odell Secara sederhana strategi dipahami sebagai suatu kelengkapan tindakan atau taktik yang terukur dan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan dengan cara tawar menawar.33 Peran strategi ini penting bagi negara berkembang terutama karena keaktifannya yang terus meningkat dalam perundingan-perundingan internasional termasuk dalam hal perdagangan. Namun, peningkatan ini bisa jadi tidak relevan jika dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki saat bernegosiasi dengan negara maju. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah negara berkembang tersebut mendapatkan bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak. Jika bisa, persoalan selanjutnya menjadi bagaimana cara atau strategi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan hasil tersebut. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dicoba dijawab oleh Odell. Namun sebelumnya, Singh mencoba menjelaskan konsesi negara berkembang yang mungkin diperoleh dalam perundingan- perundingan WTO.34 Ia mengemukakan empat faktor yang dianggap penting mengenai hal tersebut. Pertama, konstituen domestik. Kedua, agenda setting. Agenda setting merupakan proses untuk melibatkan atau tidak melibatkan isu tertentu dalam pembahasan. Dalam praktek negosiasi, pilihan pembahasan isu dalam kerangka agenda setting melibatkan faktor popularitas isu, tingkat partisipasi dalam pertemuan, serta tingkatan teknis dan kapasitas kelembagaan dari isu tersebut. Ketiga, penggunaan tekanan yang kredibel. Kapasitas aktor untuk menekan aktor lain merupakan instrumen yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pembahasan. Keempat, bentuk koalisi. Bentuk koalisi aktor sangat terkait dengan kesesuaian kepentingan yang dimiliki. Odell mendefinisikan koalisi ini sebagai sekelompok 33 34 Odell (2006), hal. 5 Odell (2006), hal.41 22 pemerintah yang memiliki kesamaan posisi dalam negosiasi dan menjalankan koordinasi yang jelas diantara mereka.35 Terkait persoalan strategi, Odel memperkenalkan dua mekanisme strategi yang bisa dilakukan dalam konteks koalisi tersebut untuk mendapatkan maksimal: strategi distributive dan integrative. Pemilihan strategi dalam sebuah mekanisme yang lebih teknis kadang sangat pragmatis sesuai tujuan yang ingin diraih. Strategi distributive bermanfaat jika pihak yang berunding benarbenar berada dalam situasi konflik sementara integrative bermanfaat saat masih bisa dikenali adanya tujuan bersama yang bisa dipahami sebagai kepentingan bersama dalam derajat tertentu. Strategi yang pertama dapat dijabarkan dengan taktik-taktik seperti: membuka penawaran yang tinggi, menolak semua konsesi, melebih-lebihkan permintaan dan prioritas minimal pihak lain, memanipulasi informasi untuk merugikan pihak lain, menyandera isu pihak lain, menyalahkan alternatif pihak lain, penuntutan secara hukum, pengancaman, dan penjatuhan hukuman. Sementara tataran teknis strategi ini antara lain meliputi: berbagi informasi secara terbuka untuk mengetahui masalah dan ancaman bersama yang dihadapi, serta menawarkan pertukaran konsesi atau tindakan yang akan menguntungkan banyak pihak. Secara sederhana strategi ini dapat dipahami sebagai upaya mendapatkan konsesi dengan kerjasama dengan pihak lain. Namun, resiko yang muncul dari strategi ini adalah ketika pihak lain malah yang diajak kerjasama mengeksploitasi keterbukaan yang ditawarkan.36 Ringkasan tawaran strategi dari Odell di atas dapat dilihat dalam bagan berikut: \ 35 36 Odell (2006), hal. 41 Odell (2006), hal. 4-5 23 Bagan 1: Strategi Integrative-Distributive Odell • • • • • • • • • • Membuka penawaran yang tinggi Menolak semua konsesi Melebih-lebihkan permintaan dan prioritas minimal pihak lain Memanipulasi informasi untuk Merugikan pihak lain Menyandera isu pihak lain, Menyalahkan alternatif pihak lain Penuntutan secara hukum Pengancaman Penjatuhan hukuman. Kegagalan perundingan putaran • • Doha Berbagi informasi secara terbuka untuk mengetahui masalah dan ancaman bersama yang dihadapiMengambil tindakan yang akan menguntungkan banyak pihak paling tidak hingga perundingan KTM VII adalah akibat dari fragmentasi yang begitu kuat antara negara maju dengan negara berkembang. Jika dikenali lebih jauh, hal ini bisa dipahami akibat distribusi konsesi yang terlalu kaku. Struktur kuasa di WTO paska KTM VII telah bergeser dengan kehadiran negara emerging power baru yang memperkuat koalisi di satu sisi dan pelemahan kuasa negara maju akibat kapasitas ekonominya yang limbung terkena hempasan krisis global di sisi lain. Ketika pada perundingan-perundingan sebelumnya negara maju tidak terlalu antusias mengejar progress perundingan Doha karena dianggap tidak terlalu bermanfaat bagi mereka, hempasan krisis membuat kondisi berbalik karena merekalah yang kemudian membutuhkan perdagangan multilateral sebagai stimulan ekonomi. Dari sini dapat dikenali ada tujuan bersama dari pihak-pihak yang berunding pada KTM IX, setidaknya agar Putaran Doha menunjukkan 24 progress demi keberlangsungan dan masa depan perdagangan multilateral. E. Argumen Utama Pencapaian Paket Bali dalam KTM IX WTO dilatarbelakangi konteks pergeseran distribusi kuasa dalam institusi WTO. Pergeseran ini terjadi karena pengaruh tiga faktor: pertama, adanya penguatan koalisi negara berkembang terutama paska dimulainya perundingan Doha sebagai bagian dari structural power; kedua, becara bertahap penguatan ini juga meningkatkan institutional power negara berkembang di WTO yang ditandai dengan progress modalitas yang dicapai; dan ketiga, kehadiran krisis semakin melemahkan structural power negara maju di WTO. Wacana yang kemudian muncul baik dalam forum WTO maupun forum ekonomi internasional yang lain adalah agar perundingan Doha segera diselesaikan sebagai bagian dari upaya recovery dari krisis. Wacana ini terus menguat yang akhirnya menjadi productive power yang berpengaruh dalam perundingan WTO. Fenomena krisis menjadi faktor tersendiri, sebagai intervening variable, yang menekan disparitas kepentingan yang ada. Sebelumnya, disparitas kepentingan ini menempatkan negara maju dan berkembang dalam posisi distributive yang kemudian bergeser lebih berintegratif seiring pergeseran kuasa dan dalam menghadapi krisis sebagai ancaman bersama. Krisis juga telah mengurangi gap dan asimetri kuasa yang berlanjut pada semakin seimbangnya posisi runding. Kecenderungan untuk semakin terintegrasinya kepentingan dan seimbangnya kuasa yang ada, dalam derajat tertentu, menjadi faktor yang memungkinkan kesepakatan perundingan dapat diraih. Pergeseran ini membuat pelaksanaan KTM IX WTO Bali berada dalam momentum yang tepat untuk menghasilkan putusan. 25 Posisi runding Indonesia selain pada substansi isu pertanian, juga terletak pada keberhasilan KTM IX agar menghasilkan putusan terkait Perundingan Doha. Diplomasi ekonomi Indonesia sendiri dalam pencapaian Paket Bali dilakukan dengan proses pencarian dukungan melalui political engagement dan technical engagement baik sebelum maupun saat pelaksanaan perundingan. Strategi mixed distributive-integrative diupayakan karena dalam perundingan KTM Bali posisi negara maju dan berkembang relatif memiliki kesamaan kepentingan, yakni agar perundingan dapat menghasilkan keputusan. F. Jangkauan Penelitian Jangkauan penulisan dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari penyimpangan pembahasan yang terlalu jauh dan tetap konsisten dengan argumen utama untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diajukan dan agar obyek penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik. Dalam lingkup WTO, melakukan analisa berbasis kelompok negara/ koalisi menjadi cara relevan untuk memahami proses perundingan karena kebiasaan negara mengelompokkan diri sesuai posisi runding mereka. Penelitian ini akan membatasi kajian pada dinamika kepentingan negara berkembang, pergeseran kuasa, serta upaya diplomasi Indonesia dalam lingkup perundingan KTM IX WTO Bali. G. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kesepakatan Paket Bali, memahami perubahan karakter konstelasi kuasa dalam WTO, serta untuk mengetahui lebih dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam pemajuan kepentingan negara berkembang pada KTM IX WTO Bali. Harapannya, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk masukan rekomendasi strategis selanjutnya, baik untuk semakin memperkuat 26 peran negara berkembang dalam forum WTO, maupun mencapai pemenuhan Doha Development Agenda, ataupun untuk semakin meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi Indonesia. H. Metode Penelitian Menetukan metode yang tepat merupakan hal yang krusial untuk mendapatkan kedalaman dan komprehensifitas dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk memahami objek penelitian yang menjadi tema penelitian. Sementara dalam teknik pengumpulan data akan digunakan pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan sekunder baik yang bersifat teoritis maupun empiris tentang obyek penelitian yang caranya diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) baik dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, artikel dan majalah, surat kabar, serta sumber internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. I. Sistematika Pembahasan Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang, pokok permasalahan, studi pustaka, landasan analisa, argumen utama, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua akan membahas gambaran obyektif WTO dan pengalaman upaya pemajuan kepentingan negara berkembang yang mencakup disparitas kepentingan dan signifikansi koalisi dalam mekanisme pengambilan keputusan, upaya pemajuan kepentingan negara berkembang era GATT dan WTO era Awal, serta analisa kuasa dalam struktur GATT dan WTO era awal. 27 Bab ketiga akan membahas pergeseran kuasa di WTO pergeseran kuasa di WTO yang mencakup deadlock Perundingan Doha dan penguatan structural power negara berkembang, faktor krisis global sebagai pelemahan structural power negara maju, dan wacana perdagangan multilateral sebagai productive power. Bab keempat akan membahas distribusi kuasa dalam negosiasi pada KTM IX WTO Bali yang mencakup penguatan institutional power negara berkembang dalam modalitas isu runding KTM IX Bali, penguatan modalitas pada masing-masing isu runding, dan pengaruh distribusi kuasa tersebut pada strategi integrative-distributive saat perundingan. Bab kelima akan membahas posisi dan peran diplomasi ekonomi Indonesia yang mencakup pengalaman indonesia dalam upaya pemajuan kepentingan negara berkembang di WTO, posisi dan kepentingan serta strategi dan peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam Perundingan KTM IX WTO Bali. Bab keenam akan memuat kesimpulan dan penutup. 28