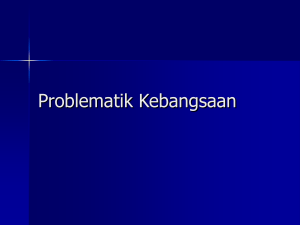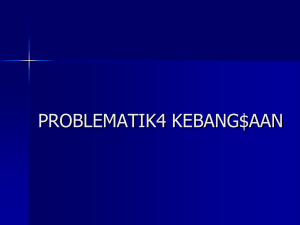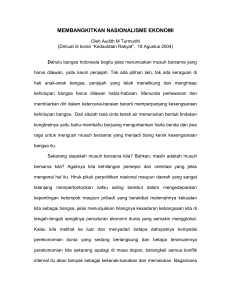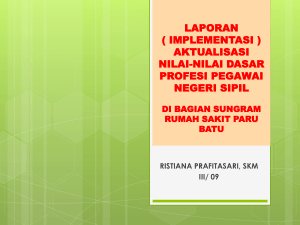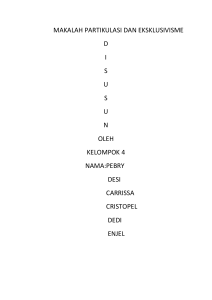BAB IV KESIMPULAN Teori modernisasi yang
advertisement

BAB IV KESIMPULAN Teori modernisasi yang menyatakan bahwa proses industrialisasi dan perkembangan ekonomi berujung pada perubahan positif dalam ranah sosial dan politik pada dasarnya mengasumsikan bahwa negara-negara maju, termasuk Jepang, tidak lagi harus direpotkan dengan permasalahan-permasalahan kesenjangan seperti diskriminasi dan xenofobia. Namun, fakta justru menunjukkan bahwa perkembangan politik dan ekonomi Jepang dewasa ini mengarah pada intoleransi dan eksklusivisme. Samuel Huntington sempat melontarkan kritikan terhadap teori modernisasi dengan memberikan catatan bahwa semakin cepat sebuah sistem masyarakat mengalami perkembangan atau modernisasi, maka institusi politik yang mewadahinya harus dengan serta merta mengimbangi dinamika tersebut demi menghindari situasi yang ia sebut sebagai “praetorianism”. Senada dengan hal tersebut, perkembangan perpolitikan Jepang dibawah komando Shinzo Abe mengarahkan Jepang menuju kemunduran. Upaya restorasi Jepang menuju identitas lamanya sebagai sebuah kekuatan imperial baru di masa modern seakan membenarkan pendapat Huntington. Pemerintah demokratis yang menjadi ciri utama negara modern menjadi sebuah antitesis dalam upaya restorasi Jepang menuju otoritarianisme dan eksklusivisme dimana sebuah rezim tidak mampu atau menolak untuk mewadahi perubahan sosial di level masyarakat dengan menafikan multikulturalisme dan menggalakkan xenofobia. Perspektif konstruktivisme memberikan asumsi-asumsi dasar yang relevan dalam memaparkan analisa perilaku xenofobia. Konsep identitas, norma, dan speech acts mampu membangun kerangka berpikir yang komprehensif ketika menjelaskan perilaku xenofobia dalam sistem masyarakat Jepang modern. Jawaban terhadap rumusan masalah dalam skripsi ini terbagi kedalam paradigma karakteristik identitas budaya sebagai landasan konstruksi norma sosial yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat, dan paradigma rezim penguasa yang berkeyakinan untuk membawa perubahan dan restrukturisasi. Kedua paradigma 51 tersebut bermuara pada dua faktor, yaitu: faktor identitas budaya sebagai landasan pembentuk norma sosial pendorong xenofobia; dan, faktor kepentingan aktor politik dalam memobilisasi isu xenofobia. Karakter identitas bangsa Jepang yang didasarkan pada “Semangat Jepang” sebagai sebuah intersubjective understanding dan harmoni sebagai norma sosial yang menjadi penjiwaan didalamnya menciptakan potensi mobilisasi terhadap suatu isu oleh penguasa melalui berbagai agenda politik eksoterik dan esoteris yang bernuansa nasionalis. Absennya landasan ideologis mutlak dalam “Semangat Jepang” membuat konsep ini bersifat ambigu. Ia tidak dapat dijadikan patokan untuk melakukan prediksi terhadap perilaku aktor, tidak pula dapat dijadikan landasan untuk membedakan keadilan dan kezaliman. Posisinya yang netral membuatnya mudah beradaptasi menjadi dorongan dalam merumuskan etika kehidupan sehari-hari hingga perumusan kebijakan pemerintahan. Sebagai nilai haluan, konsep “Semangat Jepang” berdiri diatas norma harmoni dalam wujud “perasaan bersama”. Sehingga membuat seluruh aspek kehidupan masyarakat Jepang selalu dilandaskan pada asas kolektif dalam kerangka ketertiban umum dan kepentingan bersama. Asas kolektif tersebut dimanfaatkan oleh rezim pemerintah konservatif untuk memobilisasi isu nasionalisme. Selama lebih dari lima dasawarsa terakhir ini pemerintah konservatif beriklim nasionalis di Jepang hampir tidak pernah mendapatkan interupsi dari lawan politiknya. Kalangan konservatif bertanggung jawab penuh terhadap kedigdayaan ekonomi Jepang pada masa pasca perang dan tetap dipercaya untuk memerintah dalam menanggulangi resesi ekonomi pada dasawarsa terakhir ini. Kini, disaat pemerintah Abe berhasil melakukan restrukturisasi ekonomi, mulai muncul kecenderungan perubahan arah perpolitikan Jepang menuju era nasionalisme baru. Konstituen politik Abe menginginkan agar Jepang dapat mengapresiasi kembali nilai-nilai etika tradisional Shinto yang sangat kental dengan nuansa patriotisme dan kebanggaan akan imperialisme masa lalu. Para proponen argumen tersebut akan memulai era restorasi baru dengan menghidupkan kembali aspek-aspek budaya Jepang yang diberantas oleh Sekutu pasca PD II. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran 52 bahwa masa-masa kelam era imperialisme akan kembali menghantui konstelasi perpolitikan Jepang di masa yang akan datang. Mungkin tidak dalam bentuk kebijakan politik tingkat tinggi (high-politics), seperti deklarasi perang atau ekspansi militer, namun dalam isu-isu low-politics seperti diskriminasi dan intoleransi yang akan menjadi dasar terhadap justifikasi berbagai kebijakan antiasing atau xenofobia. Xenofobia menjadi alat bagi pemerintah Jepang untuk melakukan adaptasi terhadap fluktuasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pada beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah berusaha untuk menciptakan bandwagon effect dengan menyulut sentimen tersebut agar muncul kesan pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini diperlukan demi tercapainya kesadaran kolektif masyarakat Jepang dalam menjustifikasi perilaku xenofobia sebagai tindakan yang perlu (necessary action) demi mempertahankan ketertiban umum dan kepentingan bersama. Paradigma tersebut pada akhirnya akan membuat segala preskripsi kebijakan negara terkait dengan permasalahan keamanan di kawasan dapat dengan mudah diterima oleh publik. Dengan demikian, terbukti bahwa eksistensi perilaku xenofobia dalam sistem masyarakat Jepang modern adalah sebagai alat politik untuk memobilisasi isu. Dalam berbagai studi mengenai globalisasi disebutkan bahwa era masyarakat dunia merupakan masa depan tak terelakan yang mesti direngkuh oleh setiap entitas kebangsaan. Namun, sebuah bangsa dan gelora nasionalisme yang melekat bersamanya sepertinya akan terus menjadi duri dalam daging selama beberapa waktu kedepan. Nasionalisme sebagai sebuah karakter yang terwujud dari konstruksi identitas ternyata masih menjadi kekuatan politik signifikan yang berpotensi menimbulkan eskalasi ketegangan antar negara. Penelitian mengenai perilaku xenofobia di Jepang memberikan gambaran tegas mengenai pengaruh fundamental dari aspek konstruksi identitas terhadap perilaku aktor dalam sebuah sistem. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan mampu menekankan peran konstruksi ide dan diskursus yang membentuk struktur ideasional sebagai sebuah pendekatan yang mampu menjembatani kekosongan yang tidak mampu dijelaskan oleh pertimbangan rasional dan material ala liberalisme dan realisme. 53