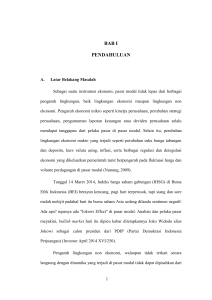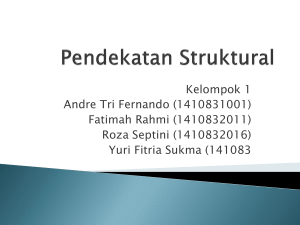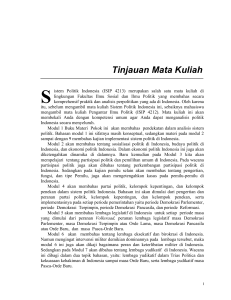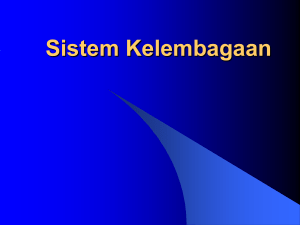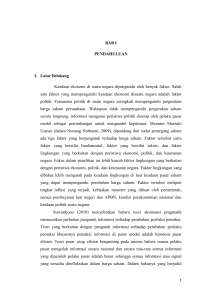Suara Perempuan Kemana? - Sistem Informasi Penelitian
advertisement

Suara Perempuan Kemana?: Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014 Oleh Arianti Ina Restiani Hunga ([email protected]; [email protected]) Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Univ. Kristen Satya Wacana Abstrak Perempuan merupakan salah satu kelompok pemilih terbesar dalam pemilu dan suara mereka menentukan calon legislatif tahun 2014. Jumlah perempuan di DPR telah meningkat dari 11,09 persen pada pemilu 2004 menjadi 17,86 persen pada pemilu tahun 2009. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari kuota perempuan 30 persen. Pada Pemilu 2014, apakah perempuan memilih calon legislatif perempuan? Pertanyaan ini menjadi relevan bila dikaitkan dengan kinerja legislatif perempuan ditengah masih banyaknya produk UU yang belum pro perempuan atau belum sensitif gender. Situasi diperburuk dengan legislatif perempuan dan pimpinan perempuan yang terbelit dalam kasus korupsi. Hal ini menjadi kontra produktif dengan upaya mencapai target keterwakilan perempuan sebesar 30 % di DPR. Salah satu hal mendasar kelemahan perempuan baik sebagai pemilih dan calon legislatif (caleg) adalah tidak memiliki pengetahuan politik yang cukup dalam upaya memperjuangkan suara mereka. Oleh karenanya, pendidikan politik pemilih perempuan menjadi penting dalam upaya menjadikan mereka pemilih yang cerdas, artinya dapat menyalurkan suara mereka secara independen dan rasional. Pada sisi yang lain adalah pendidikan politik bagi caleg dalam upaya menemu kenali persoalan dan kebutuhan perempuan, serta menuangkan dalam program strategis untuk menggalang suara perempuan. Paper ini memaparkan; 1) pentingnya pendidikan politik pemilih perempuan; 2) relevansi pendidikan politik perempuan dan peningkatan keterwakilan perempuan di DPR dalam pemilu tahun 2014. Paper ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada pemilih perempuan marginal di Kota Salatiga. Hasil awal penelitian menujukan bahwa pemilih perempuan, khususnya perempuan marginal belum mendapat perhatian yang serius dalam pesta demokrasi oleh para caleg, khususnya caleg legislatif. Sebagian pemilih perempuan belum mendapatkan pendidikan politik pemilih dalam upaya untuk membangun suara perempuan dan memecahkan persoalan perempuan dalam masyarakat. Perubahan kondisi perempuan ditentukan oleh kualitas pemilu yang dimulai sejak awal melalui pendidikan pemilih dan pemilu, serta mengawal hasilnya untuk memperjuangnya kondisi masyarakat, khususnya perempuan melalui peluang keterwakilan perempuan sebanyak 30 %. Kata Kunci: Perempuan, legislatif, pendidik politik pelimih, pemilu, gender, keterwakilan perempuan 1. Latar Belakang Bangsa Indonesia sejak tahun 1955 hingga 2014 sudah melaksanakan 11 kali pemilihan umum legislatif (pileg). Keterwakilan perempuan selama periode mengalami pasang-surut (fruktuatif), berada pada titik terendah 3,8 % pada pemilu tahun 1955 dari 488 kursi anggota legislatif. Kemudian meningkat menjadi 7,16 % pada pemilu tahun 1971 dan 8,04 % pada pemilu tahun 1982 dari 460 anggota legislatif. Meningkat menjadi 13% pad pemilu tahun 1987 dari 500 anggota legislatif dan terus mengalami penurunan menjadi 12,5% pada pemilu tahun 1992; menjadi 10,8% pada pemilu tahun 1997, dan 9% pada pemilu 1999 dari 500 anggota legislatif. Keterwakilan perempuan mengalami peningkatan kembali setelah Reformasi 1998 bersamaan dengan perjuangan dan tuntutan gerakan perempuan yang menghasilkan Ketetapan kuota 30% perempuan di parlemen, sebagai tindakan afirmatif yang diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004. Perolehan suara perempuan dalam legislatif pata tahun 2004 1 meningkatkan menjadi 11,45 % dari 550 anggota legislatif. Peroleh suara perempuan mencapai sebanyak 18,03 % dari 560 anggota legislatif pada pemilu 2009 (Fajar, Azman dan Launa, 2009; Kartikasari, Dian., 2013; sulistiyono,Joko., 2013). Secara khusus pada pemilu 2004 dan 2009, peta peroleh suara/kursi perempuan di legislatif menunjukan trend yang meningkat di DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota walaupun lebih rendah dari perolehan di DPR pusat. Secara umum angka keterwakilan suara perempuan di DPRD propinsi (33 provinsi) meningkat dari 12 % pada pemilu tahun 2004 menjadi 16% (321 dari total 2.005 anggota DPRD provinsi) pada tahun 2009. Propinsi yang tercatat berhasil memenuhi kuata 30 % perempuan di legislatif adalah Maluku berhasil menghantarkan 14 perempuan dari 45 orang (31%) (KPU, 2009). Pada aras DPRD kabupaten/kota, dari 461 kabupaten/kota memiliki total 15.750 anggota. Dari jumlah legislatif ini, terpilih sebanyak 1.857 perempuan (12%0, persentasi ini naik hampir dua kali lipat dari perolehan suara perempuan pemilu tahun 2004 sebesar 6% di DPRD kabupaten/kota. Namun ii tingkat kabupaten/kota, masih terdapat DPRD yang tidak memiliki anggota perempuan. Diperoleh data, dari 461 kabupaten/kota, terdapat 27 DPRD yang tidak ada anggota perempuan terpilih (5,9% kabupaten/kota), antara lain; terbanyak di propinsi Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Tercatat sebanyak 64 DPRD kabupaten/kota yang hanya memiliki satu anggota perempuan (Kartikasari, Dian., 2013) Dari data diatas menunjukan bahwa perjuangan panjang perempuan untuk mencapai target 30 % kuata perempuan dalam legislatif belum tercapai. Kondisi ini semakin memprihatinkan bila melihat peroleh suara perempuan hasil pemilu tahun 2014. Hasil analisis data pemilu tahun 2014 yang dilansir dalam pernyataan pers Pusat Kajian Politik – Departemen Ilmu Politik FISIP UI (PUSKAPOL FISIP UI) memaparkan bahwa perolehan suara perempuan pada pemilu tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, pada pemilu tahun 2009 sebesar 18 % menurun menjadi 14 % dari 560 anggola legislatif. Perolehan ini tentunya memprihatinkan ditengah upaya setiap komponen gerakan perempuan dan lembaga-lembaga yang pro terhadap kebijakan ini untuk mencapai kuata 30 % perempuan di parlemen. Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada pemilu tahun 2014, sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuata 30 % di parlemen yang diatur Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ada tambahan klausula yang mempertegas bahwa bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Tentunya fakta peroleh data keterwakilan perempuan tahun 2014 ini memberikan konsekuensi logis dalam peta ‘kekuatan’ parlemen dalam menghasilkan kebijakan dan produk perundang-undangan yang bisa menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih memprihatinka yang dialami perempuan dan anak, antara lain; kemiskinan, kematian ibu melahirkan dan bayi, KDRT, kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, dan 2 kekerasan kemanusiaan lainnya. Kondisi ini semakin parah bila kualitas legislatif perempuan tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah dari legislatif perempuan pada periode tahun 20092014. Hal ini menjadi masuk akal bila mengacu pada beberapa hasil penelitian dari beberapa lembaga terhadap kinerja legislatif perempuan pada periode ini. Koalisi Perempuan Indonesia (Kartikasari, Dian., 2013) memaparkan bahwa kesadaran kritis legislatif perempuan pada tataran individu dan kelompok legislatif perempuan tidak otomatis mereka mampu memberikan manfaat positif kepada perempuan sebagai basis perjuangannya di masyarakat. Faktanya produk kebijakan publik yang dibahas dan dihasilkan, termasuk alokasi anggaran dan program lebih ditujukan untuk kepentingan kelompok partai, pribadi dan kelompok, dan justru tidak pro pada perempuan dan anak. Tentunya ini semakin parah bila legislatif perempuan tersebut justru tidak memiliki kapasitas pendidikan politik dan kapasitas kritis. Temuan Women Research Institute (WRI) tahun 2012 juga menunjukan bahwa kinerja perempuan legislatif belum menunjukan mereka masih terjebak pada peran proseduran administratif dan kepentingan partai. Jurnal Perempuan (2014) menemukan bahwa sebagian besar caleg perempuan justri tidak memiliki kapasitas politik yang memadai dan basis organisasi politik. Pada sisi yang lain, ada kecenderungan media mempertontonkan beberapa legislatif perempuan yang terjebak dalam praktek korupsi tanpa menganalisis lebih ‘dalam’ mengapa mereka cenderung terjebak/dijebak dalam pusaran korupsi? Sebaliknya media kurang menyoroti atau mempublikasikan prestasi para perempuan yang memberikan kontribusi yang strategis dalam legislatif. Pemberitaan yang tidak proporsional ini menciptakan opini publik yang buruk terhadap legislatif perempuan. Juga berimbas pada pandangan yang jelek pada kiprah perempuan secara umum di ruang publik, khususnya di legislatif. Pencitraan buruk tentunya memberikan implikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap mereka. Fakta korupsi yang melanda para perempuan legislatif menunjukan bahwa mereka belum menyadari makna keterwakilannya untuk memperjuangkan kualitas hidup para perempuan di akar rumput yang seharusnya menjadi subyek perjuangannya di legislatif. Hal ini tidak terlepaskan dari pendidikan politik bagi caleg dalam upaya menemu-kenali persoalan dan kebutuhan perempuan, serta menuangkan dalam program strategis untuk menggalang suara perempuan. Paper ini memaparkan; 1) Marginalisasi Perempuan legislatif dan Pendidikan Politik Perempuan; dan 2) relevansi pendidikan politik perempuan dan peningkatan keterwakilan perempuan di DPR dalam pemilu tahun 2014. Paper ini ditulis menggunakan data penelitian yang dilakukan pada pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014. Penelitian ini merupakan riset-aksi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus berwawasan gender yang dilakukan di Kota Salatiga. Studi kasus digunakan sebagai basis unit analisis untuk melihat relialitas keterwakilan perempuan dan mencoba mengembangkan persepktif dalam konteks yang lebih luas. 3 2. Marginalisasi Perempuan legislatif dan Pendidikan Politik Perempuan Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana pemilihan legislatif dan presiden berlangsung dan peristiwa ini menentukan perjalanan bangsa pada lima tahun mendatang. Ditengah hiruk-pikuk pemilu, pertanyaan penting yang perlu diungkap dipublik adalah bagaimana dengan nasip perempuan yang merupakan pendudukan Indonesia yang lebih dari lima puluh persen pendudukan Indonesia? sejauhmana para perempuan legislatif memperjuangkan kepentingan perempuan ini dalam arus pembangunan di Indonesia? Pertanyaan ini bisa dikaitkan dengan fungsi legislasi dalam menghasilkan kebijakan terkait dengan kualitas hidup perempuan. Bila membandingkan jumlah UU yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004‐2009 dengan 2009‐2014 dan jumlah perempuan legislatif dalam periode tersebut menunjukan bahwa pada periode tahun 2004 – 2009 dengan keterwakilan perempuan sebesar 11 % atau lebih kecil dibandingklan DPR RI pada periode 2004 ‐2009 (18%), DPR RI periode 2004‐2009 lebih banyak menghasilkan undang‐undang yaitu sebanyak 7 produk UU yang merupakan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination all form Discrimination Against Women‐CEDAW) dibandingkan periode DPR RI tahun 2009-2014 yang hanya menghasilkan 3 produk UU. Lebih jelas dalam tabel 1 dibawah ini. Tabel. 1 Produk UU Periode DPR RI Tahun 2004-2009 dan 2009-2014 Sumber: Kartika, Dian (2013) dan DPR RI (2013) Kondisi lainnya diparah oleh bermunculan banyak Perda yang mendiskriminasi kaum perempuan. Komnas Perempuan (2013) menunjukan data sebanyak 342 Perda yang mendiskriminasi perempuan. Selain Perda yang mendiskriminasi perempuan, masalah lain yang hingga kini dihadapi perempuan Indonesia, seperti kekerasan seksual, hak reproduksi, perkawinan anak, pedagangan manusia, dan perlindungan lainnya. Kalyanamitra (2008) dalam hasil penelitiannya menegaskan bahwa perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat di DPR 4 (pusat dan daerah) tidak sesuai dengan harapan pemilihnya, terutama kaum perempuan. Para perempuan politisi di legislatif tidak melakukan fungsi sosial-politiknya sebagai wakil kaum perempuan. Peran mereka di legislatif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan para pemilihnya. Terkait fungsi lainnya, seperti fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalankan maksimal. Mereka tidak mengabdi kepada kepentingan kaum perempuan, tetapi kepada kepentingan pemodal dan parpol masing-masing serta egoism diri sendiri (korupsi, kolusi, nepotism, dll). Hal ini bisa dikaitkan dengan fakta empiri yang menunjukan target MDGs tahun 2015 terkait penekanan angka kematian ibu dan anak, indeks IPM, indeks gender masih menjadi persoalan. Sebagai contoh, tahun 1991, angka kematian ibu melahirkan 390/100 ribu kelahiran, tahun 2007 menjadi 228/100 ribu kelahiran, namun tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 359/100 ribu kelahiran. Dari paparan diatas menunjukan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif tidak otomatis meningkatkan produk per-UU yang dihasilkan DPR RI menjadi lebih banyak dan lebih adil gender. Kemampuan perempuan legislatif memainkan peran dalam legislatif terkait erat dengan pendidikan politik perempuan yang memadai. Modal ini menjadi penting dalam menghadapi sistem DPR RI yang lebih didominasi oleh para laki-laki legislatif. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Poltracking Indtitute (2014) menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja legislatif. Hanya 12% responden yang menyatakan kinerja DPR baik. Penilaian kinerja tersebut dianggap rendah kualitas dan kuantitasnya didasarkan atas tiga fungsi utama mereka, yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam legislatif dapat dikaitkan dengan kualitas hidup perempuan dan anak yang masih memperihatinkan. WRI (2012) memaparkan fakta ini, antara lain; angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Vietnam1. Human Development Report (HDR) tahun 2011 menempatkan Indonesia pada rangking 124 atau sedikit lebih baik dari negara Vietnam dan Kamboja. Namun, Gender Inequality Index (GII) Indonesia berada pada rangking 100 dan di bawah GII Vietnam yang berada pada rangking 48. Dua dari indikator GII ini adalah AKI dan persentase perempuan yang duduk di parlemen. Rangking GII Indonesia dan Vietnam yang demikian menunjukkan bahwa AKI Indonesia 240/100.000 kelahiran sedangkan Vietnam adalah 56/100.000 kelahiran. Sementara persentase perempuan di parlemen Vietnam adalah 25,8%, sedangkan Indonesia adalah 18% 2. Fakta lainnya, selain itu, World Economic Forum3 pada tahun 2009 mengeluarkan Global Gender Gap Index (GGI) berdasarkan data Gender Empowerment Measurement (GEM), Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) tahun 2007. Apabila kita lihat situasi Indonesia, maka akan terlihat GGI 0,62. Angka ini diperoleh dari data Indonesia 1 Noerdin, Edriana. Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia, (Jakarta: Women Research Institute, 2011). 2 Summary Human Development Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All, (UNDP, 2011),hal. 19. 3 Power, Voice and Rights. A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific, (UNDP, Macmillan, 2010). 5 untuk GEM 0,4, GDI 0,72 dan HDI 0,73. GEM (0,4) mencerminkan kesempatan ekonomi dan politik perempuan yang cenderung lebih rendah dari GDI (0,72). Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perempuan mempunyai kapasitas, mereka belum tentu memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan kapasitasnya. Meskipun di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, pencapaian dalam kaitannya dengan kondisi dan posisi perempuan di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara. Posisi Indonesia rangking HDI lebih tinggi dibandingkan Vietnam, namun situasi dan posisi perempuannya masih lebih rendah terutama dalam hal AKI dan persentase perempuan di parlemen. Kualitas hidup perempuan dan anak yang dipaparkan diatas, diperkirakan tidak banyak berubah bila hasil pemilu 2014 tidak memberikan hasil yang signifikan. Berdasarkan analisis perbandingan data hasil pemilu tahun 2009 dan 2014, Puskapol FISIP UI (2014) memaparkan dua hasil temuan, pertama, analisis hasil pemilu secara umum menyimpulkan; (1) kekuatan partai politik didaerah berubah dari Partai Demokrat pada pemilu tahun 2009 menjadi terpusat pada persaingan antara PDIP dan Golkar. PDIP sebagai pemenang pemilu, unggul dalam perolehan suara di 36 dapil, disusul Golkar yang unggul di 25 dapil. Berturut-turut partai lainnya: PKB unggul di 6 dapil, Gerindra dan Demokrat masing-masing unggul di 4 dapil, kemudian PAN dan Nasdem masing-masing unggul di 1 dapil. Sementara PKS, PPP, dan Hanura tidak unggul di seluruh dapil; (2) Kecenderungan semakin meningkat pemilih yang memberikan suara untuk nama caleg pada surat suara yang terlihat dari sebanyak 70 % coblos nama caleg dan 30 % pada partai politik. Kondisi tersebut hampir sama dengan hasil Pemilu 2009, yaitu 69.03% untuk caleg dan 30.96% untuk partai; (3) mayoritas pilih caleg laki-laki yang terlihat dari data sebagian besar (76,69%) memilih caleg laki-laki dan sisanya (23,31%) memberikan suara untuk caleg perempuan. Persentase perolehan suara caleg perempuan tersebut masih jauh dari pencalonan perempuan yang mencapai 37% pada Pemilu 2014 ini. Di sisi lain, sekalipun masih jauh lebih rendah dari suara yang diberikan untuk caleg laki-laki, jika dibandingkan data Pemilu 2009 maka ada peningkatan sedikit perolehan suara caleg perempuan (dari 22.45% menjadi 23.31%); (4) Perolehan tertinggi caleg perempuan dari partai PPP (23,33%) dan terendah dari partai PKS (13,20%). Adapun rincian peroleh suara caleg perempuan menurut partai, antara lain; PPP (23,33%), Nasdem (19,74%), Demokrat (18,56%), PAN (17,60%), Golkar (16,22%), PDIP (15,89%), Gerindra (15,50%), Hanura (13,57%), PKB (13,23%), dan PKS (13,20%); (4) ada 20 daerah pemilihan dengan suara caleg lebih dari 30 % dan sebanyak 4 daerah pemilihan yang perolehan suara dibawah 30 %, antara lain; Aceh 1 (10.61%), Jateng II (9.15%), kemudian Bali (8.9%), dan NTT 1 (10.51%). Kedua, analisis hasil pemilu dilihat dari suara perempuan, antara lain; (1) caleg perempuan terpilih sebanyak 79 orang atau 14%. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 yaitu 103 orang atau 18%. Data ini menarik disimak bila melihat tingkat pencalonan dan perolehan riil suara antara pemilu tahun 2009 dan 2004. Pada pemilu 2004 pencalonan perempuan mencapai 37 % dan angka ini lebih tinggi dari pemilu 2009 sebesar 6 33,6% namun pereoleh suara perempuan pemilu 2014 justru lebih rendah (14%) dibandingkan pemilu tahun 2009 (18%). Tingkat pencalonan pemilu 2014 sejalan dengan adanya Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur minimum 30% pencalonan perempuan dalam Daftar Calon Tetap di setiap dapil DPR/DPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan.; (2) Sebagian caleg perempuan yang diperkirakan terpilih didominasi oleh “wajah-wajah baru” di parlemen. Dari 103 anggota perempuan di DPR RI periode 2009–2014, hanya ada 36 orang yang diperkirakan terpilih kembali. Dengan kata lain, hanya sekitar 34% perempuan petahana lolos kembali menjabat di DPR RI.; (3) ada kesenjangan yang lebar antara perolehan suara perempuan dengan perolehan kursi perempuan. Pada pemilu 2009 tercatat 22.45% rata-rata perolehan suara perempuan untuk DPR RI dengan 18% hasil perolehan kursi perempuan. Pada pemilu 2014 tercatat perkiraan 23.42% perolehan suara perempuan untuk DPR RI namun hasil perolehan kursi hanya mencapai sekitar 14%. Hal ini terkait dengan kebijakan internal partai dalam penentuan kursi celeg perempuan. Perempuan cenderung diletakan dalam nomer urut besar dan hal ini menunjukan komitmen internal partai lebih sekedar pemenuhan syarat administratif dalam tahap pencalonan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan/UU.; (4) Keterwakilan perempuan dalam DPR RI tersebar dalam 10 partai dengan prosentasi 3 % sampai 24 %. Tiga prosentasi tertinggi dari partai PPP (24%), golkar (22%) dan Demokrat (22%) dan terendah dari PKS (3%).; (5) kenaikan perolehan kursi partai tidak selalu diikuti oleh kenaikan persentase kursi perempuan. Perolehan keterwakilan perempuan dari partai-partai relatif fruktuatif dan cenderung menurun. Demokrat adalah partai yang mengalami penurunan paling signifikan yaitu tahun 2009 sebanyak 36 kursi menjadi 12 kursi perempuan. Namun secara agregat perolehan kursi perempuan dari partai Demokrat relatif stabil dari 24 % menjadi 22 % (turun 4 %). Penurunan dialami 5 partai lainnya yaitu PKS (2 %), PDI Perjuangan (7%), PKB (8%), Gerindra (10%), dan Hanura (16%). Dari sembilan partai yang dapat dibandingkan, hanya ada tiga partai yang persentase perkiraan perolehan kursi perempuannya naik, yaitu: PPP (11%), PAN (3%), dan Golkar (2%). Adapun peningkatan kursi perempuan di DPR RI diperkirakan paling tajam mencapai 11% berasal dari PPP. Penurunan paling drastis mencapai 16% yakni pada Partai Hanura.; (6) Basis rekrutmen para perempuan legislatif belum mempertimbangkan kapasitas, basis partai, dan akar rumput sebagai modal dalam melakukan peran mereka di legislatif. Hal ini terlihat dari sebagian besar perempuan legislatif (39%) yang terpilih pada pemilu 2014 menggunakan jaringan kekerabatan dengan elit politik (laki-laki). Hal ini terlihat dari hubungan yang dimiliki terkait sebagai isteri, anak, menantu, dan sejenisnya dengan pejabat politik dan atau pejabat partai. Sisanya, sebanyak 13 % dari elit ekonomi, 7% dari publik figur (artis), 7% dari LSM/aktifis, 8% dari anggota DPR/DPRD, dam 26% merupakan kader partai; (7) Data sementara berdasarkan perkiraan keterpilihan caleg perempuan di DPR RI menunjukkan dominasi jaringan kekerabatan dengan elit politik sebagai basis rekrutmen caleg hingga 7 mencapai 39%. Persentase ini diperoleh melalui penelusuran latar belakang masing-masing perempuan terpilih dan didapati sebagian besar dari mereka adalah adik, kakak, ataupun istri dari penguasa/pejabat politik serta petinggi partai politik yang mencalonkan mereka. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini sebenarnya telah ditemukan juga pada hasil pemilu 2009 dimana sekitar 42% perempuan terpilih sebagai anggota DPR RI merupakan bagian dari perpanjangan tangan penguasa/pejabat politik serta petinggi partai. Penurunan signifikan tercatat pada basis keterpilihan sebagai selebriti/figur populer, yakni dari 25% di tahun 2009 menjadi 7% di tahun 2014.; (8) dominasi basis keterpilihan caleg perempuan yang berlandaskan hubungan kekerabatan dengan politik sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2014 (sekitar 40% lebih) mengindikasikan stagnasi sempitnya landasan rekrutmen caleg perempuan oleh partai. Fakta ini semakin menegaskan ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan, kekuatan material, dan pelanggengan dominasi laki-laki (patriarkhi) terhadap perempuan. Lebih lanjut, situasi ini bermuara pada terkonsentrasinya kekuasaan elit politik dan elit ekonomi di tangan segelintir orang dalam parlemen atau praktek politik oligarki.; (9) kehadiran caleg perempuan adalah hasil dari kebijakan afirmatif yang lebih formalitas administratif sejauh partai dapat meloloskan diri untuk ikut dalam pemilu dan bukan substantif. Perjuangan keterwakilan perempuan dalam politik memiliki dua makna. Pertama, untuk mewujudkan pemenuhan Hak Politik Perempuan dalam tatanan kehidupan Demokrasi‐yaitu Hak memilih dan dipilih serta hak untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik . Kedua ditujukan untuk mewujudkan keadilan gender secara substantif (Subatantive Equality), yaitu keadilan bagi laki‐laki dan perempuan dalam pembangunan, yaitu keadilan dalam menjangkau (akses), ikut serta (partisipasi) , dan pengambilan keputusan (kontrol) dalam pembangunan serta keadilan dalam penguasaan dan penikmatan hasil‐hasil pembangunan. Dengan demikian maka keadilan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan, merupakan keadilan dari sisi proses dan hasil. Bukan sekedar memperjuangkan jumlah dan proses. Namun hasil pemilu 2014 diatas memberikan sinyal awal bahwa masyarakat belum bisa berharap banyak dengan kiprah perempuan legislatif di parlemen karena kehadiran mereka baru sebatas administratif prosedural. Selain kelemahan rekrutmen yang sudah dipaparkan diatas, kelemahan lain perempuan legislatif adalah kapasitas politik agar bisa berkiprah secara substansial dalam parlemen. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pendidikan politik bagi legislatif agar bisa mengambil peran aktif baik di parlemen maupun pada basis massa di akar rumput, khususnya perempuan marginal yang jumlahnya jauh lebih banyak. 2. Relevansi Pendidikan Politik Perempuan dan Keterwakilan perempuan Keterwakilan perempuan dalam legislatif masih menjadi paradoks karena secara formal dan substrantif dibutuhkan agar perempuan turut terlibat secara aktif dalam perubahan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui legislatif. Namun 8 realitasnyannya langkah kearah ini masih menemui banyak kesulitan. Sistem politik yang masih didominasi oleh sistem patriarkhi menjadi faktor mendasar yang menjadi kendala perjuangan ini. Sistem ini dilanggengkan tidak saja oleh elit politik tetapi juga diterima dan dilanggengkan oleh masyarakat secara luas, termasuk didalamnya perempuan. Oleh karenanya kebijakan kuota 30 % di parlemen diharapkan dapat memecahkan persoalan ini. Gagasan ini sebagai bentuk sebagai bentuk konkrit dari pergeseran politik gagasan (politics of ideas) ke arah politik kehadiran (politics of presence) yang cetuskan Phillips, Anne (1995). Pertanyaan klasik yang ada dimasyarakat adalah apakah keterwakilan perempuan secara otomatis bisa merubah kondisi perempuan dan anak menjadi lebih baik? Logika ini juga sejalan dengan pandangan bahwa secara teoritis, laki-laki bisa saja menjadi representasi perempuan karena laki-laki mempunyai kapasitas untuk menyampaikan gagasan atau advokasi atas nama perempuan. Bahkan berkembang argumentsi bahwa perspektif gender yang dimiliki laki-laki diangap mampu mewakili perempuan. Namun logika ini sulit diterima karena faktanya sudah berkali-kali pemilu yang dilalui Indonesia, perempuan selalu terlupakan sebagai bagian dari agenda penting yang layak diperhatikan ditengah kompleksitas masyarakat. Susilastika, Dewi Haryani (2014) menggunakan gagasan Prikin (1995) menjelaskan bahwa keterwakilan dalam konteks pemilu mempunyai makna simbolis menjadi wakil/delegasi/juru bicara bahkan kuasa yang menggantikan orang yang memilih mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam mempengaruhi pengambulan keputusan. Jadi bila dilihat dalam gambaran data yang dipaparkan diatas maka secara umum kehadiran laki-laki legislatif, apalagi perempuan legislatif tidak mampu memenuhi makna simbolis ini yang berkahir pada pengambilan keputusan untuk mewakili mereka yang telah memilih. Data diatas menunjukan bahwa dalam pemilu tahun 2009 dan 2014, lebih banyak pemilih yang memberikan suaranya kepada caleg dibandingkan kepada partai. Hal ini menunjukan bahwa keterwakilan simbolis masih menjadi suatu yang penting. Sejalan dengan teori representasi deskriptif yang menegaskan bahwa tingkat kepercayaan pemilih sangat dipengaruhi oleh karakteristik wakil rakyat yang kasat mata, antara lain; jenis kelamin; asal/etnis, kepercayaan dan hal-hal lain yang dianggap serupa/sam. Hal ini juga bermakna bahwa pemilih akan memilih wakilnya yang menurut mereka memiliki ‘sesuatu’ yang hampir mirip dengan mereka yang pada akhirnya dianggap bisa memahami dan bisa membantu memecahkan persoalan dan kebutuhan mereka. Susilastika, Dewi Haryani (2014) mengutip argumentasi Mansbridge (2000) memberikan ilustrasi bahwa wakil rakyat laki-laki akan menghadapi kesulitan untuk memahami persoalan dan kebutuhan perempuan terkait dengan fungsi reproduksi mereka, seperti; pentingnya tempat penitipan anak bagi mereka selama mereka bekerja. Persoalannya, laki-laki tidak mengalami hal ini secara konkrit karena mereka memiliki peran gender yang berbeda dengan perempuan di masyarakat. Dalam masyarakat, lakilaki tidak pernah merasakan beban bagaimana harus bekerja dan sekaligus memelihara anak (beban ganda). Hal yang sama, sulit bagi laki-laki memahami pentingnya perlindungan bagi 9 perempuan korban perkosaan karena laki-laki tidak memiliki fungsi reproduksi dan implikasi spikis-sosial menjadi korban perkosaan. Oleh karenanya kehadiran perempuan secara fisik dapat dimaknai sebagai kehadiran simbolis yang berimplikasi pada kehadiran secara substantif dalam memecahkan persoalan dan kebutuhan perempuan yang kompleks. Dalam konteks ini menjadi sangat relevan untuk memperjuangkan kuota keterwakilan perempuan 30 % di parlemen. Tentunya argumentasi ini masih bisa dipertanyakan karena perempuan legislatif tidak hanya merepresentasikan perempuan. Phillips, Anna (1991) mengatakan bahwa realitasnya perempuan sulit untuk mereprestasikan dirinya dalam konteks perempuan semata. Sebagai makluk sosial, perempuang bisa dimaknai secara jamak, misalnya partai, komunitas dan kelompoknya yang tidak lepas dari banyak kepentingan. Kondisi ini semakin diperparah bila perempuan legislatif ternyata tidak mengetahui persoalan dan kebutuhan perempuan secara praktis dan strategis. Dalam riset-aksi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Studi Gender UKSW pada pemilu 2009 yang lalu, sebagian besar calon legislatif perempuan tidak mengetahui secara jelas persoalan dan kebutuhan perempuan baik praktis dan strategis. Semakin parah lagi mereka juga tidak menguasai secara dalam tugas-tugasnya sebagai calon legislatif. Hal ini menjadi persoalan mendasar seorang perempuan legislatif yang bisa menjalan peran untuk mewakili pemilih yang telag memilihnya. Persoalan inilah yang mendorong gagasan tentang affirmative action melalui kebijakan pemberian kuota pada perempuan untuk bisa mempercepat pertambahan jumlah mereka di parlemen (Dahlerup dan Freidnvall, 2003). Harapannya melalui kebijakan kuota ini, kehadiran perempuan secara kuantitas-simbolis yang relatif cukup bisa memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan perubahan pada sistem parlemen yang didominasi oleh para laki-laki (Lovenduski dan Karam, 2002). Tentunya persoalannya belum selesai sampai disini karena ada persoalan lainnya adalah bagaiman hal ini bisa terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana mendorong kehadiran yang simbolis-kuntitatif menjadi kehadiran/keterwakilan yang kualitatifsubstantif. Tentunya persoalan ini terarah pada bagaimana kapasitas perempuan legislatif sebagai modal yang mereka miliki untuk bisa berperan kualitatif-substantif. Melihat hasil penelitian Kartika, Dian (2013), Jurnal Peremuan (2014) dan Puskapol FISIP UI (2014) menunjukan bahwa sebagian besar (70%) caleg perempun tidak memiliki pengalaman dan pendidikan politik yang memadai maka harapan kehadiran/keterwakilan perempuan secara kualitatif-substantif menjadi sulit diharapkan. Kehadiran perempuan legislatif pada periode 2014-2019 diprediksi tidak berubah menjadi lebih baik bila melihat sebagian dari perempuan legislatif adalah legilatif pada periode 2009-2014. Menurunnya peroleh kursi perempuan di legislatif tahun 2014 ini menjadi bentuk konkrit dari turunnya kepercayaan para pemilih, khususnya perempuan terhadap caleg perempuan. Bila diletakan dalam gagasan Phillips, Anna (1991) maka dapat dilihat bahwa pemilih perempuan tidak melihat secara simbolis dan prinsip bahwa mereka bisa diwakili atau mewakilkan suaranya (persoalan dan kebutuhan) pada para perempuan legislatif. Dalam konteks yang lain bisa artikan 10 bahwa perempuan legislatif tidak berbasis secara substantif pada perempuan di akar rumput atau dalam istilah yang berbeda mereka ‘tercabut’ atau terputus dari ‘akar rumput”. WRI (2012) menambhakan untuk memahami konsep representasi Phillips, Anna (1991) mengatakan penting untuk mengkombinasikan apa yang disebut sebagai politics of presence dan politics of ideas. Ada empat hal utama yang dibutuhkan untuk mendorong keterwakilan: (1) representasi simbolik, yaitu memasukkan kelompok-kelompok marjinal menjadi bagian penting agar mereka bisa bersuara; (2) bagaimana seorang calon legislatif dapat membawa isu-isu yang tidak pernah diangkat sebelumnya; (3) untuk mengubah pola representasi, ada kebutuhan dari kelompok di luar parlemen untuk berkontribusi terhadap kebijakan; dan (4) adanya beberapa isu yang belum masuk dalam agenda yang disuarakan partai politik. Anne juga menambahkan bahwa perempuan memiliki sejarah panjang sebagai entitas yang mengalami marjinalisasi, diskriminasi, dan subordinasi sehingga mereka harus diikutsertakan untuk mengubah alur representasi yang ada. Argumentasi diatas bisa dijelaskan dalam skala yang lebih mikro dalam konteks penelitian yang dilakukan oleh Progdi Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UKSW pada menjelas pemilu dan pemilu tahun 2014 yang lalu di Kota Salatiga. Percakapan dengan ibu Suti demikian: “saya ini orang kecil, hanya pemulung sampah yang hari-hari bekerja memperoleh makan dari hasil menjual sampah. Kami disini sangat kurang diperhatikan, padahal tempat kami tempat menampung sampahnya orang kota. Kami selalu sulit air setiap musim kemarau panjang, tidak bisa menyekolahkan anak, tidak ada pekerjajan lain selain sampah. Desa kami hanya ramai didatangi caleg bila menjelang pemilu. Para caleg, ya laki-laki dan perempuan sama saja, memberikan janji-janji. Kami tidak tahu partai, kami tahu orangnya saja. Kalau sering beri bantuan ya menang. Misalnya; dusun saya dapat bantuan pembangunan rumah yang difasilitasi oleh bapak (X). Saya tahu dari RT dan RW bahwa Bapak (X) anggota DPR lama tetapi tidak tahu partai apa. Kami diberi gambarnya dan diminta ingat-ingat, itu yang dicoblos. Pemilu tahun 2009, disini ada perempuan legislatif yang menang, ya juga bisa menang karena sering kasih bantuan. Juga bapaknya pemborong rumah, ada orang desa sini yang dikasih kerjaan. Tapi sudah lama tidak kesini, tidak tahu apa tidak ‘nyalon’ lagi. Seperti saya ini orang ‘kecil’ ya manut apa kata suami dan Pak RT, pilih sesuai yang disuruh. Disini tidak ada yang melakukan sosialisasi pemilu. Bila ada mungkin masyarakat tidak tertarik, lha a a tidak mudeng, paling ya janji-janji. Lha mending saya kerja, malah dapat duit” Cuplikan wawancara lainnya dengan Mbak Desi, seorang Pemandu Karaoke di Kota salatiga. “saya tidak punya rencana untuk ikut pemilu tahun 2014 nanti. Saya tidak merasa itu penting untuk saya sebagai pemandu karaoke. Lha, kami ini siapa toooo mbak, orang tidak ‘dianggap’. Kalau mereka jadi, opo yo beri kami bantuan? Mbok yo jalan ditempat kami didepan ini lho diperbaiki, bila baik yo tamu yang kesini bisa banyak. Untungnya bukan untuk kami saja, yo untuk semua. Kami bekerja keras malam sampai pagi, resikonya yo banyak, ada tamu yang kasar, sok dan tidak menghargai. Saya tidak tahu kalau milih caleg, yo hidup kami jadi lebih baik. jadi saya tidak semangat. Tapi mungkin kalau 11 pilpres, saya mau pilih karena mau coblos Jokowi. Saya joblos karena ia orang sederhana dan kayaknya mau memperhatikan orang ‘kecil”. Disini tidak ada sosialisasi pemilu dan saya tidak tahu calegnya siapa saja. Saya juga merantau dari luar Jawa”. Cuplikan wawancara lainnya dengan 3 orang caleg perempuan (Mbak Tia, Mbak Mer, dan Mbak Yul) yang bisa dirangkum seperti ini. “Mbak Tia memulai diskusi, “saya sebenarnya tidak tertarik menjadi caleg tetapi ditawarin pengurus partai katanya untuk memenuhi syarat 30 %. Saya tidak tahu persis apa pentingnya keterwakilan perempuan. Mbak Mer dan Yul juga mengutarakan hal yang sama, bedanya Mbak Mer ditawarin bapaknya yang dekat dengan elit partai, dan mbak Yul oleh suaminya. Mbak Yul menambahkan, kaya suami saya coba-coba saja, bila katut lumayan khan gajinya besar. Mbak Mer tidak kalah antusiasnya menambahkan ,” lho kalau saya justru dipaksa-paksa sama bapak saya, katanya sekedar syarat-syarat, biar partai lolos. Secara bergantian mereka mengungkapkan, ‘bagaimana ya mbak, kami khan bukan orang partai, tidak tahu politik, tidak tahu mau sosialisasi apa.” Dari cuplikan wawancara diatas, nampak pemilih maupun caleg perempuan tidak memiliki pertimbangan sendiri memilih siapa. Selain itu ia juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup memahami arti suaranya dalam pemilu dana bagaimana keterhubungan perempuan dari ‘akar rumput’ dan perempuan legislatif dalam konteks peran mereka sebagai legislator. Dari data diatas, menunjukan bahwa pendidikan politik bagi perempuan pemilih dan caleg menjadi penting dalam upaya membangun kapasitas pribadi dan koneksinas antar perempuan dalam perannya yang berbeda. Lemahnya aspek ini menentukan terpilihnya perempuan sebagai legislatif baik di DPRD RI dan PDRD. Pada aras nasional sudah dipaparkan datanya diatas, menunjukan perolehan suara perempuan turun signifikan menjadi 14 % pada tahun 2014 dari 18 % pada pemilu tahun 2009. Hal sana terjadi di DPRD Kota Salatiga, hasil rekap KPUD Kota Salatiga tahun 2014 menunjukan legislatif perempuan turun dari 7 kursi pada pemilu tahun 2009 menjadi 4 kursi pada tahun 2014. Bahkan yang cukup mencegangkan adalah perempuan legislatif perempuan (sebut saja Ibu Debi) ang mempunyai kinerja yang bagus bahkan dikenal luas karena kiprahnya yang positif dalam pengawasaan anggaran, dan memiliki pendidikan politik yang baik justru harus berhenti dan tidak mencalonkan lagi pada periode pemilu 2014 karena mekanisme partainya. Usahanya untuk mendongkarak suara partai dan caleg perempuan sebagai kolega (sebut saja Ibu Mona) yang dikaderkan tidak berhasil mengantarkan kadernya dan juga partainya memperoleh kursi di DPRD Kota Salatiga. Pentingnya pendidikan politik pemilih dan caleg menjadi pengalaman peneliti pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Pendidikan politik yang dilakukan pada pemilu 2009 pada celeg perempuan di Kota Salatiga mampu mendongkrak kursi perempuan menjadi 7 atau 25 % dari total kursi legislatif di Kota Salatiga. Dialog politik yang dibangun diantara caleg perempuan bisa merumuskan agenda politik caleg perempuan yang menjadi program kampanye mereka 12 dalam pemilu tahun 2009 yang lalu. Pada sisi yang lain, pendidikan politik pemilih yang dilakukan di 4 Kecamatan di Kota Salatiga, mampu membangun dialog caleg dan perempuan pemilih yang dituangkan dalam kontrak politik sebagai media pembelajaran bersama dalam mengawal suara perempuan di legislatif (Hunga, dkk., 2009). Peroleh suara perempuan di Kota Salatiga tahun 2009 juga diperkuat oleh adanya beberapa program LSM, universitas, puslit, dan aliansi antar LSM peduli suara perempuan yang melakukan program pendidikan politik baik pra pemilu, pemilu, maupun pasca pemilu. Upaya LSM dan universitas (termasuk PPSG-UKSW) merupakan bagian upaya keterwakilan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila dikaitkan dengan argumentasi Phillips, Anna (1991) maka pendidikan politik diletakan dalam konteks bagaimana perempuan menjadi pihak yang sentral menyadari dan mengambil langkah strategis untuk bisa memperoleh kesempatan merepresentasikan suara perempuan di akar rumput. Juga pada sisi yang lain perempuan dari ‘akar rumput’ mempunyai koneksitas yang substantif untuk bisa menyuarakan persioalan dan kebutuhannya, serta memperoleh ‘ruang’ untuk memenuhannya melalu perempuan legislatif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan strategis di legislatif. Dalam hal ini pendidikan politik atau pendidikan politik perempuan diarahkan, antara lain; membentuk kesadaran politik, komitmen, kemampuan untuk berpartisipasi secara cerdas dan kritis dalam peristiwa-peristiwa politik sebagai bagian dari komponen masyarakat dalam negara yang demokrasi. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, teater, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Pilihan metode pendidikan ini secara teoritis menentukan efektifitas pendidikan yang diberikan. Sebagai contoh pendidikan pemilih yang dilakukan oleh progdi Sosiologi-FISKOM UKSW bekerjasama dengan Teater Rakyat STAIN Salatiga yang mengusung judul “Demokrasi Ala Warung Kopi” yang dipentaskan di desa yang merupakan area pemanpungan sampah akhir (TPA) kota Salatiga. Dalam pementasan ini para pemain memainkan dua aktor yang berbeda karakter dan motivasinya maju sebagai caleg dalam pemilu tahun 2014. Sebut saja Pak Broto memainkan tokoh arogan yang mengandalkan uang untuk membeli suara kelompok masyarakat marginal di lokasi sekitar TPA Kota Salatiga. Sebaliknya, tokoh caleg perempuan, sebut saja Ibu Tantri, melakukan observasi dan analisis sebagai acuan ia menawarkan program pemecahan bagi masyarakat ini. Ibu tantri tidak datang dengan uang tetapi tawaran kerjasama dan program sebagai agendanya pada saat jadi legislatif. Pementasan ini mendapat sambutan yang riuh, ada terikan mencibir sikap Pak Broto yang arogan. Kata-kata yang keluar secara spontan dari penonton antara lain ‘korupsi, pencuri uang, ojo dipilih, bohooooog, dst’. Teriakan sebaliknya buat Ibu Tantri pada saat berkomunikasi dengan penonton, misalnya; butuh pekerjaan, kesehatan gratis, hidup bu Tantri, dst.”. 13 Dari gambaran pementasan diatas, menunjukan bahwa dialog yang cerdas yang dikemas sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat, memudahkan penonton memahami apa makna pemilu dan bagaimana mereka memberikan suaranta dengan cerdas dan bertanggung jawab. Metode pendidikan pemilih yang dikemas secara sederhana dan sesuai dengan konteks setempat memudahkan masyarakat paham dan bisa menerima pendidikan politik pemilih yang ingin disampaikan. Namun demikian, metode pendidikan yang sudah dikemas dengan baik belum menjamin bahwa pemilih bisa mengkonkritkan pilihannya dengan cerdas karena banyak faktor diluar mereka yang lebih kuat mengatur masyarakat marginal. Fakta yang patut disimak adalah maraknya money politic maka metode pendidikan politik tidak berjalan efektif. Hal ini terungkap dalam diskusi dibawah ini dengan Ibu Tatik di Kota Salatiga. “Sosialisasi pemilu disini setahu saya tidak ada. Juga mungkin memang tidak ada karena sudah ada kapling-kapling para caleg melalui tim suksesnya. Seperti disini, sudah jelas siapa yang menang. Masyarakat tidak lihat partainya tetapi calegnya. Ada persaingan caleg dalam partai yang sama, yaitu kuatkuatan uangnya. Sing banyak uang ya pasti jadi. Masyarakat tidak tahu apa itu program caleg apalagi partai. Pokok’e yang kasih bantuan banyak, pasti menang. Sosialisasi pemilu pakai ‘pertujuan4” dan musik sebenarnya masyarakat suka (remen5) karena menghibur dan memberikan pengetahuan bagaimana mencoblos. Caleg biasanya datang ke tempat kami bila dekat pemilu. Saya tidak tahu program para caleg. Saya ya bigung karena terlalu banyak partai dan caleg. Tapi ya itu, caleg yang beri bantuan sudah pasti menang. Itu sudah diatur bapak-bapak, juga suami saya. saya lebih semangat bila pilihan presiden nantinya. Saya sudah punya pilihan (JOKOWI) karena orangnya baik, suka menolong, dan jujur. Saya tahu dia dari partai PDI Perjuangan tetapi pada saat caleg, kami tidka pilih partainya tetapi pilig caleg lain yang sudah beri bantuan. Tidak enak bila tidak jadi, nanti diminta kembali bantuannya.” Pada saat peneliti menanyakan, apakah tahu bagaimana caranya agar calon presidennya bisa dapat melaju ke pilpres. Ibu Tatik menjawab cepat, “tidak tahu”, karena tidak ada sosialisasi. Oya, apa ada aturannya to? Pada saat peneliti mengatakan bahwa partai pilihannya bisa memperoleh 25 % atau lebih, ibu Tatik nampak kaget dan spontan mengatakan o o o o, olah bagaimana lagi (piye maneh)”. Dari penggalan diskusi dengan sumber informasi menunjukan bahwa pilihan-pilihan perempuan lebih banyak ditentukan oleh laki-laki dan mereka mempunyai pengetahuan yang terbatas. Hal lainnya adalah calon legislatif perempuang tidak mempunyai koneksi yang baik 4 Yang dimaksud adalah pendidikan pemilih menggunakan teater rakyat yang dilakukan oleh FISKOM UKSW menjeng pemilu dengan Judul “Demokrasi ala Warung Kopi”. 5 Bahasa Jawa yang artinya senang. 14 dengan calon pemilih perempuan. Mereka menemui calon pemilih dan memsosialisasikan programnya. Tidak terkoneksinya caleg perempuan sebenarnya terkait erat pada pendidikan politik mereka yang juga terbatas. Penggalan diskusi diatas dengan caleg perempuan menjadi gambaran konkrit betapa mereka tidak paham peran mereka yang sebenarnya di legislatif bila mereka terpilih. 3. Kesimpulan Perolehan suara/kursi perempuan dilegislatif pada pemilu tahun 2014 menurun menjadi 14 % dibandingkan dengan pemilu tahun 2009 sebesar 18%/. Penurunan ini signifak dan terjadi pada saat UU pemilu terkait keterwakilan 30 % justru semakin tegas. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat sebagian besar dari perempuan legislatif yang terpilih tidak memiliki kapasitas dan pendidikan politik yang memadai sebagai modal dirinya memainkan peran-peran dalam parlemen. Fakta ini diperkirakan lebih memburuk kinerja legislatif tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebenarnya buruk dibandingkan kinerja legislatif tahun 2004. Fakta ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan selama ini lebih menunjukan keterwakilan yang formalistik administratif dan belum kehadiran yang substrantif. Anjloknya peroleh suara perempuan dilegislatif sebagai bentuk ‘terputusnya’ atau tidak adanya koneksi yang sinergis antara perempuan di akar rumput dan legislatif perempuan; Hal ini terjadi karena ketidak berdayaan perempuan dalam sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam legislatif masih dibutuhkan dan perlu terus diperjuangkan. Hal ini menjadi penting terus diperjuangkan dalam upaya menciptakan perubahan kualitas hidup perempuan dan anak sebagai wujud perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Pendidikan politik perempuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perempuan menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan persolaan keterwakilan perempuan yang substransif dalam legislatif. Namun disadari pendidikan politik menghadapi tantangan maraknya praktek politik uang sebagai bentuk politik transaksional yang didominasi oleh para laki-laki legislatif. Daftar Pustaka Alawiah, Juwito dan Syfa Syarifa., 2009. POLA KOMTJNIKASI POLITIK PEREMPUAI\ DALAM PEMILU. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1., N0.2, Oktober 2009. Hunga, Arianti Ina. R.H., dkk., 2009. Pendidikan Politik Pemilih dan Pemilu untuk Perempuan Marginal di Propinsi Jawa Tengah. Pusat Penelitian dan Studi Gender Univ. Kristen satya Wacana bekerjasama dengan UNDP. 15 Kartikasari, Dian., 2013. “Keterwakilan Perempuan, Ketidakadilan dan Kebijakan Keadilan ke depan. Disampaikan dalam Konferensi INFID , Pembangunan Untuk Semua, Jakarta 26‐27 November 2013 Launa dan Azman Fajar,2009.Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna, atau Turut Mewarnai? Pengantar Redaksi. Jurnal Sosial Demokrasi KPU Kota Salatiga., 2014. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Legislatif Terpilih dan Partai Politik Kota salatiga. Kalyanamitra, 2008. LAPORAN HASIL PENELITIAN. KUALITAS PEREMPUAN POLITISI DI LEGISLATIF. Kalyanamitra Jakarta Komnas Perempuan. Laporan Independen Komnas Perempuan mengenai Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia, 20072011. Jakarta: 2011, hal. 17. Subono, Nur Iman., 2014. Partisipasi Perempuan, Politik Elektoral dan Kuota: Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan? dalam Perempuan Politisi. Jurnal Perempuan N0 81. Jurnal perempuan Jakarta Mar’iyah, Chusnul., 2011. “Keterwakilan Perempuan Melalui Kuota: Pengalaman Indonesia dan Argentina”. Jurnal Afirmasi. Jakarta: WRI. 2011. Perludem., 2014. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014. Rekomendasi atas Hasil Workshop Knowledge Sharing Pitkin, Hanna. 1967. The Concept of Representation. University of California Press. PUSKAPOL FISIP UI, 2014. Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014: OLIGARKI POLITIK DIBALIK KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN. PERNYATAAN PERS Pusat Kajian Politik – Departemen Ilmu Politik FISIP UI Susilastuti, Dewi Haryani., 2014. Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik Gagasan ke Politik Kehadiran dalam Perempuan Politisi. Jurnal Perempuan N0 81. Jurnal perempuan Jakarta Women Research Indtitute, 2012. PENELITIAN KEBIJAKAN. perempuan Anggota DPR-RI dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 16