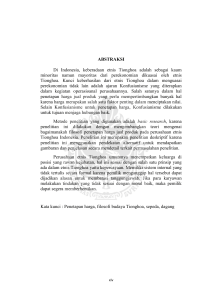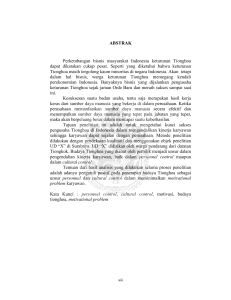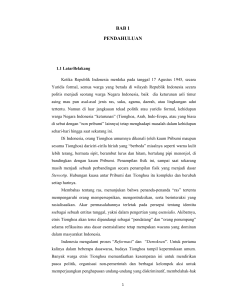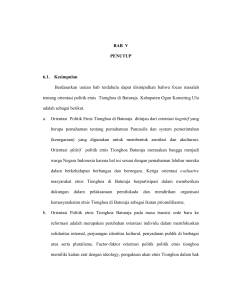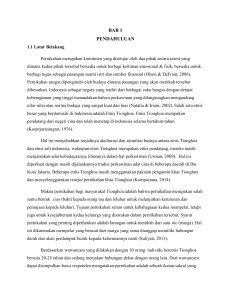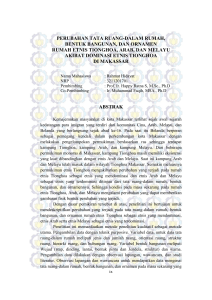makalah - gereja dan politik
advertisement
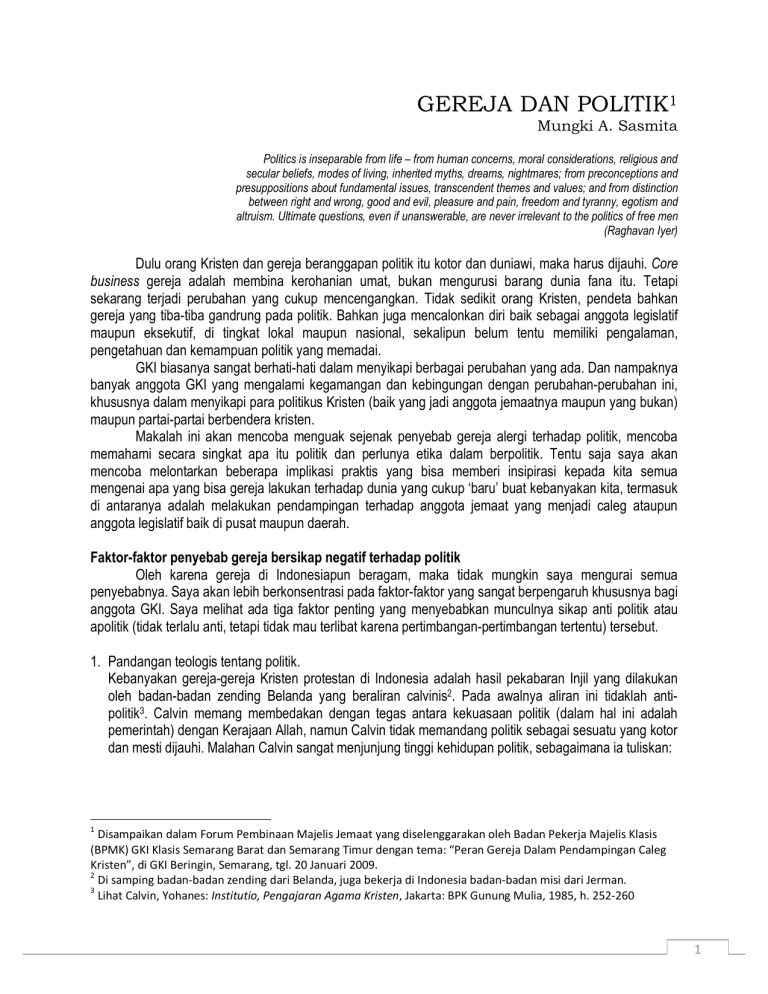
GEREJA DAN POLITIK1 Mungki A. Sasmita Politics is inseparable from life – from human concerns, moral considerations, religious and secular beliefs, modes of living, inherited myths, dreams, nightmares; from preconceptions and presuppositions about fundamental issues, transcendent themes and values; and from distinction between right and wrong, good and evil, pleasure and pain, freedom and tyranny, egotism and altruism. Ultimate questions, even if unanswerable, are never irrelevant to the politics of free men (Raghavan Iyer) Dulu orang Kristen dan gereja beranggapan politik itu kotor dan duniawi, maka harus dijauhi. Core business gereja adalah membina kerohanian umat, bukan mengurusi barang dunia fana itu. Tetapi sekarang terjadi perubahan yang cukup mencengangkan. Tidak sedikit orang Kristen, pendeta bahkan gereja yang tiba-tiba gandrung pada politik. Bahkan juga mencalonkan diri baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, di tingkat lokal maupun nasional, sekalipun belum tentu memiliki pengalaman, pengetahuan dan kemampuan politik yang memadai. GKI biasanya sangat berhati-hati dalam menyikapi berbagai perubahan yang ada. Dan nampaknya banyak anggota GKI yang mengalami kegamangan dan kebingungan dengan perubahan-perubahan ini, khususnya dalam menyikapi para politikus Kristen (baik yang jadi anggota jemaatnya maupun yang bukan) maupun partai-partai berbendera kristen. Makalah ini akan mencoba menguak sejenak penyebab gereja alergi terhadap politik, mencoba memahami secara singkat apa itu politik dan perlunya etika dalam berpolitik. Tentu saja saya akan mencoba melontarkan beberapa implikasi praktis yang bisa memberi insipirasi kepada kita semua mengenai apa yang bisa gereja lakukan terhadap dunia yang cukup ‘baru’ buat kebanyakan kita, termasuk di antaranya adalah melakukan pendampingan terhadap anggota jemaat yang menjadi caleg ataupun anggota legislatif baik di pusat maupun daerah. Faktor-faktor penyebab gereja bersikap negatif terhadap politik Oleh karena gereja di Indonesiapun beragam, maka tidak mungkin saya mengurai semua penyebabnya. Saya akan lebih berkonsentrasi pada faktor-faktor yang sangat berpengaruh khususnya bagi anggota GKI. Saya melihat ada tiga faktor penting yang menyebabkan munculnya sikap anti politik atau apolitik (tidak terlalu anti, tetapi tidak mau terlibat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu) tersebut. 1. Pandangan teologis tentang politik. Kebanyakan gereja-gereja Kristen protestan di Indonesia adalah hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh badan-badan zending Belanda yang beraliran calvinis2. Pada awalnya aliran ini tidaklah antipolitik3. Calvin memang membedakan dengan tegas antara kekuasaan politik (dalam hal ini adalah pemerintah) dengan Kerajaan Allah, namun Calvin tidak memandang politik sebagai sesuatu yang kotor dan mesti dijauhi. Malahan Calvin sangat menjunjung tinggi kehidupan politik, sebagaimana ia tuliskan: 1 Disampaikan dalam Forum Pembinaan Majelis Jemaat yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) GKI Klasis Semarang Barat dan Semarang Timur dengan tema: “Peran Gereja Dalam Pendampingan Caleg Kristen”, di GKI Beringin, Semarang, tgl. 20 Januari 2009. 2 Di samping badan-badan zending dari Belanda, juga bekerja di Indonesia badan-badan misi dari Jerman. 3 Lihat Calvin, Yohanes: Institutio, Pengajaran Agama Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985, h. 252-260 1 …kekuasaan politik itu adalah suatu panggilan, yang tidak hanya suci dan sah di hadapan Allah, tetapi juga yang paling kudus dan yang paling terhormat di antara semua panggilan dalam seluruh lingkungan hidup orang-orang fana4 Penghormatan ini berangkat dari pemikiran bahwa politik atau pemerintahan merupakan sarana untuk menegakkan apa yang baik dan benar, melindungi orang-orang yang benar dan menghukum siapa saja yang bersalah. Dengan adanya kekuasaan politik, diharapkan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, sehingga setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan tenteram. Dalam kaitan dengan fungsi politik ini pulalah, Calvin berbicara tentang hubungan gereja dan negara. Bagi Calvin negara berfungsi melindungi dan memajukan gereja yang benar serta memerangi dan mencegah penyebaran agama-agama palsu. Namun bukan berarti bahwa Calvin menganut paham “gereja-negara”. Pemahaman Calvin lebih didasari atas pertimbangan bahwa bagaimanapun juga negara mesti tunduk pada firman Allah. Itu sebabnya mereka harus turut serta dalam memajukan gereja yang benar. Sekalipun Calvin dan calvinis mula-mula tidaklah anti-politik, namun kita perlu menyadari bahwa calvinis yang masuk ke Indonesia telah diwarnai pula oleh semangat pietisme yang sangat berpengaruh di Eropa – khususnya di Belanda dan Jerman – sejak abad 18.5 Pietisme yang berasal dari kata Latin pietas yang artinya “kesalehan” sangat menekankan tiga hal utama: kelahiran kembali, pertobatan dan kekudusan hidup (baca: moralitas). Dari situ kita bisa melihat ciri lain dari semangat pietisme ini, yaitu individualistik. Kesalehan individu mendapatkan tekanan yang sangat besar. Akibatnya kesalehan sosial tidak mendapat tempat sama sekali dalam semangat pietisme ini. GKI yang berawal dari komunitas Kristen Tionghoa juga menerima paham-paham pietis dari penginjilpenginjil dari Cina daratan. Dua tokohnya adalah John Sung dan Dzao Tse Kuang. Para penginjil itu adalah anak-anak jaman kebangkitan (revivalism) yang memiliki akar kuat pada semangat pietisme tersebut.6 Maka dapatlah kita pahami bila kemudian warga GKI khususnya dan orang-orang Kristen di Indonesia pada umumnya tidak terlalu berminat terhadap kehidupan politik. Apalagi dengan melihat berbagai contoh nyata betapa praktik-praktik politik seringkali jauh dari kekudusan hidup. Maka terlibat dalam kehidupan politik hanya akan mencemari kekudusan orang-orang Kristen. 2. Trauma politik dan double minority complex Pengalaman traumatis yang amat memengaruhi sikap dan pandangan politik kebanyakan orang Kristen adalah peristiwa tahun 1965. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan sebutan G30S/PKI7 itu telah memakan korban jiwa yang amat besar – konon antara ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Ditambah lagi 4 Ibid. h. 256 Pietisme atau juga disebut puritanisme mulai muncul di kalangan kaum calvinis di Inggris pada abad 17. Kemudian semangat pietisme ini masuk ke Belanda dan Jerman. Pietisme lahir sebagai reaksi atas kondisi keagamaan di Eropa yang dinilai terlalu rasionalistik, sehingga mengabaikan aspek perasaan dan praktik hidup kudus di kalangan umat beriman. Lihat: Berkhof, H. DR dan DR. I.H. Enklaar: Sejarah Gereja, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, h. 218. Haroutunian melihat aspek lain dari kebangkitan semangat pietisme ini, yaitu adanya kekuatiran bahwa gereja semakin kehilangan pamornya di kalangan umat beriman. Lihat: Haroutunian, Joseph: Piety vs Moralism, New York & Evanston: Harper Torchbook, Harper & Row Publishers, Inc, 1970, h. 3-14. 6 Wijaya, Yahya: Church-State-Market Relations in the Context of Indonesia. Artikel ini pernah dimuat dalam Asia Journal of Theology (21:2) 2007. Saya mendapatkan artikel itu secara pribadi dari penulisnya. Kutipan yang saya maksudkan terdapat pada halaman 3 dari softcopy yang saya terima. Selanjutnya untuk kutipan-kutipan atas artikel tersebut saya akan mengacu pada halaman yang tertera dalam softcopy. 7 Penyebutan “PKI”, sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi di kalangan ahli-ahli sejarah. Di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, masalah itu hanya dibicarakan di bawah permukaan, tetapi di era reformasi ini, apa yang dulu taken for granted sekarang mulai dipermasalahkan. 5 2 dengan sikap represif dari penguasa Orde Baru yang militeristik dan premanistik, menyebabkan munculnya pandangan di sebagian besar masyarakat Indonesia – termasuk orang-orang Kristen – bahwa terlibat dalam kehidupan politik hanya mencari masalah saja. Bahkan tidak jarang saya mendengar informasi yang mengatakan bahwa banyak Majelis Jemaat yang menegur pendetanya dengan keras ketika pendetanya mulai terlibat dalam diskusi atau seminar-seminar yang berbau politik. Banyak Majelis Jemaat yang kuatir kalau-kalau keterlibatan pendetanya dalam politik akan menyusahkan gerejanya. Dan GKI adalah gereja orang-orang Tionghoa. Baru dalam beberapa puluh tahun terakhir ini keanggotaan GKI menjadi lebih multi-etnis, sekalipun anggota jemaat beretnis Tionghoa masih tetap mayoritas. Orang-orang Tionghoa menghadapi dilema yang tidak mudah dalam kaitan dengan kehidupan politik ini.8 Dalam masa Orde Baru, orang-orang Tionghoa telah mengalami character assassination secara komunal,9 sehingga secara keseluruhan warga Tionghoa merasa menjadi strangers in their own land – orang-orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Keberadaannya sebagai orang Kristen yang Tionghoa menimbulkan perasaan double minority complex, kelompok terasing karena minoritas ganda yang disandangnya. Buffer politic10 yang dijalankan oleh Orde Baru serta trauma politik yang dialaminya11 (lihat juga butir 2 di atas) secara efektif dan sistematik telah menanamkan ketakutan yang besar di kalangan masyarakat Tionghoa. Sikap ini mau tidak mau pasti memengaruhi juga sikap gereja (khususnya GKI) terhadap kehidupan politik. 3. Budaya Confusianisme Yahya Wijaya dalam artikelnya yang menyoroti soal hubungan antara gereja, negara dan pasar dalam konteks Indonesia12 mengatakan bahwa sikap apolitik di kalangan orang Tionghoa berakar pada paham Confusianisme13 dan pada gilirannya juga pertimbangan dan kepentingan bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Wong Siu-lun (dikutip oleh Yahya Wijaya) terhadap para pebisnis di Singapura dan Hongkong menunjukkan bahwa merekapun memiliki tendensi untuk bersikap apolitik. Padahal mereka jelas-jelas tidak memiliki trauma politik sebagaimana dialami oleh orang Tionghoa di Indonesia. Bagi para pebisnis menjaga relasi yang baik dengan penguasa adalah mutlak penting kalau mereka ingin bisnisnya lancar dan tidak dipersulit. Dengan bersikap sebagai good boy, diharapkan penguasa akan 8 Bila anda berminat membaca mengenai masalah ketionghoaan di Indonesia, ada banyak referensi yang dapat dimanfaatkan, terutama tulisan-tulisan sinolog Leo Suryadinata. 9 Onghokham dalam kata pengantar untuk buku Leo Suryadinata mengutip tulisan DR. Wang Gungwu yang mengatakan bahwa tidak ada suatu golongan Tionghoa perantauan di dunia yang sesudah perang dunia kedua mengalami keguncangan seberat golongan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Lihat Dr. Onghokham: Pengantar (Sejarah Berkembang, Adakah Harapan bagi Minoritas), dalam DR. Leo Suryadinata: Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: PT Grafitipers, 1986, h.ix. 10 Buffer politic adalah term yang dilontarkan oleh Dr. Arief Budiman dalam sebuah ceramahnya untuk menyebut praktik adu domba yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Bila ada gejala rakyat mengalami ketidak-puasan terhadap pemerintah, maka pemerintah segera merekayasa suatu kerusuhan etnis. Dan yang selalu dijadikan korban adalah kelompok masyarakat yang paling lemah: masyarakat Tionghoa. Dengan demikian masyarakat Tionghoa selalu difungsikan menjadi buffer (penahan) yang bisa ‘menghadang’ luapan ketidak-puasan massa atas pemerintah dan mengalihkan kemarahan massa tersebut ke masyarakat Tionghoa. Dari potensi konflik vertikal (rakyat vs pemerintah) menjadi konflik horisontal (antar kelompok masyarakat yang berbeda etnisnya). 11 Trauma politik yang dialami oleh orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak ketimbang yang dialami oleh sukusuku lain. Orang-orang Tionghoa tidak hanya mengalami tindakan represi pada jaman Orde Baru saja, tetapi juga jaman kolonial Belanda dan Jepang, juga di jaman Orde Lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. 12 Op.cit.5, h. 2-3. 13 Dalam hirarki sosial menurut Confusianisme, para pedagang menduduki tempat yanglebih rendah ketimbang pemerintah. Maka mereka harus menghormati para penguasa ketimbang bersikap kritis. Lihat op.cit. 5 3 membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan iklim bisnis mereka. GKI yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang Tionghoa sedikit banyak tentulah dipengaruhi juga oleh sikap dan pandangan ini. Politik: negatif ataukah positif? Pandangan yang mengatakan bahwa politik itu kotor dan berlumuran dosa sebenarnya keliru, namun dapat dipahami. Sepak terjang (sebagian) aktor politik yang seringkali tidak memberikan citra positif atas dunia ini ikut menguatkan paham yang keliru ini. Padahal sebenarnya politik sama dengan bidangbidang lain dalam kehidupan manusia. Ia bahkan juga dapat disamakan dengan kegiatan pelayanan gerejawi. Sesuatu yang mestinya mulia dan luhur, namun bukankah pelayanan gerejawi pun dapat diselewengkan untuk maksud-maksud yang tidak terpuji? Raghavan Iyeh14, yang dikutip pada awal makalah ini, menegaskan ketidak-terpisahan politik dalam aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Politik, dalam pandangan Iyeh, bukan melulu soal kekuasaan, tetapi jauh lebih dalam lagi. Ia berkaitan sangat erat dengan moralitas, impian, harapan dan ketakutan manusia, bahkan juga menyangkut cara hidup manusia. Secara epistemologi, politik berasal dari kata polites 15 artinya penduduk (citizen). Terkait dengan itu, kata politics mempunyai arti (a) the art or science of government atau (b) the art or science concerned with guiding or influencing governmental policy dan (c) the art or science concerned with winning and holding control over government. Juga dikemukakan makna lain dari kata politics tersebut yaitu the total complex of relations between people living in society. Sedangkan political berarti characterized by shrewdness in managing, contriving and dealing; sagacious in promoting a policy; shrewdly tactful. Kamus Wikipedia memberikan definisi politik sebagai berikut: Politics is the process by which groups of people make decisions. The term is generally applied to behavior within civil governments, but politics has been observed in all human group interactions, including corporate, academic, and religious institutions. It consists of “social relations involving authority or power” and refers to the regulation of a political unit, and to the methods and tactics used to formulate and apply policy.16 Jadi politik sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola, menyusun maupun membuat kesepakatan dalam kerangka kehidupan bersama sebuah masyarakat. Aktifitas politik ditujukan untuk menciptakan dan melaksanakan pranata-pranata sosial dan normatif yang memungkinkan masyarakat manusia hidup dengan tertib, aman, tenteram dan sejahtera. Agar supaya efektif dibutuhkanlah otoritas atau kekuasaan. Karena politik pada akhirnya berhubungan dengan kekuasaan, maka tidak mengherankan bila politik juga disalah-gunakan semata untuk mengejar dan merebut kekuasaan belaka. Dan semakin besar sebuah kekuasaan digenggam, seperti kata Lord Acton, semakin besar pula tendensi penyimpangannya. Tanpa kontrol dan pembatasan, akan mudah terjadi abuse of power. Untuk itu tidak hanya dibutuhkan sistem dan aturan main politik (konstitusi, undang-undang dan perangkat hukum yang lain) yang baik, tetapi juga dibutuhkan etika politik. Sejarah manusia sudah membuktikan bahwa ketika politik dijalankan tanpa etika, maka yang terjadi bukanlah kemaslahatan masyarakat umum, melainkan krisis keadilan, kemanusiaan dan ketentraman. 14 Tulisan Iyer ini dikutip oleh Anwar Barkat, lihat: Anwar Bakat: Reconstruction of political ethics in an Asian perspective, dalam: Srisang, Koson: Perspectives on Political Ethics, an ecumenical enquiry, Switzerland: WCC Publications, 1983, h. 53. 15 Meriam-Webster’s 11th Collegiate Dictionary (format CD 3.0 version) 16 http://en.wikipedia.org/wiki/Politic 4 Etika Politik dan konteksnya Dalam etika, konteks memainkan peranan amat penting. Konteks kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah bagian dari Asia. Salah satu ciri khas dari Asia adalah peran agama yang menonjol dalam kehidupan masyarakatnya. Anwar Barkat,17 seorang pakar ilmu politik dari Pakistan, dalam konsultasi yang diadakan oleh Dewan Gereja-gereja Dunia tentang etika politik di Cyprus mengatakan bahwa sekalipun Asia memiliki keragaman budaya, agama dan pengalaman sejarah, namun ada beberapa kesamaan yang cukup menonjol di antara bangsa-bangsa di Asia, yaitu: sebagian besar pernah menjadi wilayah jajahan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika, dan kedua, agama memainkan peranan penting dalam masyarakat Asia. Bagi masyarakat Asia, sumber etika politik tidaklah berasal dari filsafat-filsafat positivistik sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Eropa, melainkan dari agama atau refleksi filosofis yang berorientasi pada agama. Berbeda dengan masyarakat barat yang amat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Yudeo-Kristen, sehingga masyarakatnya relatif lebih homogen, tidak demikian dengan Asia. Dalam keberagaman Asia, khususnya Indonesia setiap tradisi keagamaan tentunya harus mendapat ruang yang cukup untuk menyatakan pemikiran-pemikiran etisnya. Upaya-upaya dari kelompok tertentu yang mencitacitakan negara-agama, atau mendominasi kebijakan-kebijakan politik dengan warna tradisi keagamaan tertentu, sudah pasti tidak akan menciptakan kondisi yang adil, benar dan dengan demikian juga tidak akan menciptakan perdamaian. Hal ini perlu saya tekankan di sini, karena kegairahan sebagian umat Kristen dan gereja terhadap perpolitikan, nampaknya juga sedikit banyak diwarnai oleh cita-cita yang sektarian. Acapkali kampanyekampanye – baik terselubung maupun terang-terangan – yang dilakukan oleh beberapa politikus Kristen di dalam gereja sangat menekankan janji “akan memperjuangkan kepentingan Kristen”. Karena dianggap selama ini orang-orang Kristen menghadapi penindasan dan ketidak-adilan.18 Politik yang beretika seharusnya tidak hanya memikirkan satu kelompok tertentu saja, apalagi kalau itu kelompoknya sendiri. Karena politik menyangkut hajat hidup orang banyak, maka sudah seharusnya politik itu diarahkan dan dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua orang, atau at least sebanyak mungkin orang. Pada titik inilah politik membutuhkan sumbangan etika dari berbagai tradisi keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya. Karena konsep tentang yang baik, adil, benar dan menyejahterakan bisa berbeda-beda antara satu tradisi keagamaan dengan tradisi keagamaan yang lain.19 Selain dari keberagaman tadi, Indonesia juga memiliki aspek lain yang harus diperhatikan secara serius yaitu kemiskinan. Indonesia seperti juga sebagian besar negara-negara Asia yang lain adalah negara yang masih dililit oleh kemiskinan yang hebat. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kebijakan politik pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat secara luas melainkan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal – dalam maupun luar negeri – sehingga kesejahteraan yang diharapkan mengalir dari keberhasilan pembangunan tersebut tidak terjadi. Alih-alih mengalir, yang terjadi hanyalah menetes, itupun dalam skala yang amat terbatas. Ideologi pembangunan yang seperti ini masih diperparah dengan berkembangnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Alhasil jumlah orang yang menikmati hasil-hasil pembangunan itupun semakin terbatas. Kejatuhan rezim Orde Baru tidak berarti berakhirnya ideologi pembangunan dan praktik korupsi di negara kita. Aktor-aktor politik yang dulunya bernaung dengan nyaman di bawah payung Orde Baru sampai sekarang hampir-hampir tak tersentuh oleh 17 Op.cit.13, h. 50-69. Contoh yang paling sering diangkat adalah sulitnya mendapatkan ijin mendirikan gedung gereja. 19 Bandingkan dengan pendekatan yang diusulkan oleh Yahya Wijaya dalam Op.cit. 6, h.8. Yahya Wijaya mengatakan bahwa pendekatan partnership adalah yang paling tepat untuk konteks Indonesia baik dalam kaitan hubungan agama-negara, maupun dalam bidang agama-ekonomi. 18 5 hukum. Dan bahkan beberapa dengan tenangnya terus berusaha kembali ke panggung politik melalui berbagai kesempatan, baik pilkada maupun pemilu nasional. Berakhirnya rezim represif Orde Baru, telah menyebabkan terbukanya kran kebebasan. Dalam eforia kebebasan ini ada kecenderungan yang amat kuat untuk menjadi kebebasan yang liar. Berbagai kekerasan secara telanjang dipertunjukkan di depan umum oleh berbagai elemen masyarakat, sehingga tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan bahwa saat ini bangsa kita juga tengah mengalami krisis ketertiban (crisis of order). Situasi semacam ini sungguh sangat kondusif bagi kelahiran kembali dan berkembangnya kelompok-kelompok ekstrim terutama yang berbaju agama. Aparat keamanan dan ketertiban serta aparat hukum terkesan tak berdaya menghadapi semuanya itu. Bila kondisi ini dibiarkan maka bukannya demokrasi yang akan terwujud melainkan kekacauan. Dan itu akan memicu dua kemungkinan yaitu kembalinya rezim militeristik atau pemerintahan diktator atas nama agama. Krisis-krisis tersebut di atas juga menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa kita sebagai sebuah bangsa tengah menghadapi krisis kepribadian dan moral yang amat serius. Apa yang pernah dibangun oleh para founding fathers kita, seolah-olah sudah lenyap. Masalah kepribadian dan moral bukan masalah yang bisa disepelekan. Semua bangsa yang maju dan beradab akan selalu memiliki landasan kepribadian dan moral yang tinggi. Tanpa kepribadian dan moral yang baik, bangsa kita akan berjalan menuju ke jurang kehancuran dan menjadi bangsa paria di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa dunia. Etika politik Kristen Pada umumnya etika Kristen mendasarkan diri pada pemikiran Paulus sebagaimana terdapat dalam Roma 13:1-7. Di situ Paulus berbicara tentang hubungan umat beriman dengan pemerintah (kaisar). Namun krisis Naziisme telah menyentak pemikiran etika politik kristen di Eropa, dan menyadarkannya bahwa perikop itu saja tidaklah memadai untuk sebuah dasar etika politik.20 Karena terbukti dalam sejarah bahwa tidak selalu penguasa itu representasi dari Allah. Tidak tertutup kemungkinan penguasa politik justru menjadi representasi dari kuasa Iblis ketimbang Allah. Oleh karena itu pendasaran biblis atas etika Kristen perlu mulai dievaluasi dan direvisi. Tidak berarti bahwa perikop itu tidak berlaku lagi. Melainkan diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendasar dan komprehensif. Dalam kesempatan yang amat terbatas ini tidak mungkin kita membicarakan secara mendetil etika Kristen dalam bidang politik. Oleh karena itu di sini hanya akan dipaparkan beberapa prinsip dasar dalam perumusan etika Kristen dalam bidang politik. Untuk itu saya akan merujuk pada hasil-hasil konsultasi yang diadakan oleh WCC di Cyprus yang membicarakan masalah etika politik tersebut. Dalam konsultasi itu disepakati beberapa hal penting dan mendasar berkaitan dengan pokok pembicaraan kita, yaitu:21 1. Perlunya pemahaman yang holistik mengenai kesaksian alkitabiah Seperti telah disinggung di atas bahwa pendasaran etika Kristen hanya pada bagian-bagian tertentu saja dari kesaksian Alkitab, tidaklah memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan dan pemahaman yang lebih holistik atas isi Alkitab. Pendekatan yang holistik akan menolak segala bentuk absolutisasi atas bagian-bagian tertentu dalam Alkitab, menerima dan menggunakan secara kreatif kepelbagaian kontekstual, dan fokus utama pada kesaksian biblis tentang Yesus Kristus dan Kerajaan Allah. Penekanan atas keutuhan dan keseluruhan Alkitab tidak berarti mengabaikan berbagai tekanan yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. 2. Keterkaitan antara yang historis dengan yang eskatologis Umat beriman yang hidup di dalam dunia ini berada dalam konteks sejarah. Ia bagian dari sejarah dan dengan demikian menjadi bagian pula dari realitas politik yang ada baik lokal maupun global. Namun 20 21 Yoder, John Howard: The Politics of Jesus, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975, h. 193-214. Report of the Cyprus consultation, dalam op.cit. 13, h. 21-22 6 pada saat yang sama setiap orang beriman juga hidup dalam janji dan pengharapan eskatologis. Tugas umat beriman adalah menjaga ketegangan ini secara kreatif. Benar bahwa kedua realitas ini berbeda; segala tindakan manusia dalam sejarah bersifat relatif, dan semuanya itu harus dilihat dalam terang tindakan Allah yang akan menggenapi janji eskatologisNya. Oleh karena itu segala tindakan politik umat beriman juga harus senantiasa dilakukan dalam terang dan mengacu pada janji eskatologis Allah yang akan menghadirkan KerajaanNya secara sempurna. 3. Dua simbol kunci Dua simbol kunci penting dalam rangka memahami etika politik Kristen adalah, pertama, simbol yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu komunitas perjanjian (covenant community). Simbol ini melambangkan hubungan yang baik antara Allah dengan umatNya. Dan relasi tersebut menjadi dasar dari pemahaman (alkitabiah) tentang keadilan, kebenaran dan perdamaian (shalom). Simbol yang kedua adalah kerajaan atau komunitas mesianis (messianic community or kingdom). Sekalipun simbol kedua ini berakar pada simbol yang pertama, namun ia juga memiliki identitas dan integritas sendiri. Kerajaan mesianis adalah komunitas mesianis dari suatu perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dan ia mengarah pada suatu komunitas tanpa kekuasaan untuk mendominasi, dan komunitas yang di dalamnya janji Allah untuk tinggal di antara umatNya tergenapi, sehingga umat memerintah bersama dengan Mesias. Manifestasi dari komunitas ini bermuara pada salib Kristus, Mesias yang menderita. Inilah simbol eskatologis dan ia tidak bisa diubah begitu saja ke dalam ideologi politik dalam realitas historis. Tetapi simbol ini penting untuk menjaga agar supaya umat beriman tetap memiliki perspektif kritis dalam menafsirkan sejarah politik dan memelihara suatu visi yang berpengharapan yang melampaui pengharapan-pengharapan historis. Implikasi-implikasinya Berdasarkan prinsip-prinsip etis tersebut di atas, maka keterlibatan orang kristen dalam kehidupan politik hendaknya didasari atas penghayatan: 1. Kekuasaan sebagai anugerah Allah. Kekuasaan bukan sesuatu yang buruk. Ia hendaknya dipahami sebagai anugerah Allah. Dan setiap anugerah Allah haruslah dipergunakan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dengan demikian jabatan dan kekuasaan itu dipandang sebagai kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat dan kepada Tuhan. 2. Keberpihakan kepada yang lemah Para politikus Kristen dipanggil memiliki keberpihakan kepada yang lemah, karena dua alasan penting, yaitu, pertama, kelompok masyarakat inilah yang seringkali menjadi korban penindasan, ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan. Keberpihakan mereka tidak boleh dilandasi oleh sentimen-sentimen yang bersifat primordial (suku, ras atau agama). Dan kedua, kelompok inilah yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia, khususnya mereka yang lemah secara sosial-ekonomi. Namun keberpihakan itu juga tidak membuta, dalam arti bahwa aturan dan hukum tidak berlaku bagi kelompok ini. 3. Memiliki visi dan misi yang berorientasi pada rakyat dan kerajaan Allah Visi dan misi para politikus Kristen hendaknya tidak hanya dibatasi oleh lingkup dan waktu. Maksudnya kiprahnya dalam dunia politik tidak hanya dibatasi oleh konstituennya saja (kelompok pemilihnya) ataupun jangka waktu ia memiliki jabatan itu. Melainkan hendaknya terarah pada perwujudan cita-cita Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi para politikus Kristen juga sekaligus adalah agen-agen eskatologis. Ia seharusnya ikut serta dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah (keadilan, kebenaran, perdamaian dan keutuhan ciptaan) sampai dengan pemenuhannya. 4. Mendorong perubahan yang benar dalam masyarakat Indonesia 7 Para politikus Kristen hendaknya juga menjadi agen-agen perubahan. Untuk itu dibutuhkan keteladanan sikap dan perilaku yang baik. Setiap politikus Kristen harus berani mengatakan “tidak” atas semua tawaran, bujukan atau strategi-strategi yang dapat membuatnya jatuh pada tindak korupsi, kolusi ataupun nepotisme; menjauhi segala bentuk premanisme dan menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen. Rekomendasi bagi tindakan praktis 1. Gereja perlu terlibat dalam politik dalam arti yagn luas. Ia mengikuti dengan seksama berbagai perkembangan politik. Gereja juga harus berani menyatakan aspirasi politiknya yang kritis serta dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan moral-etis kristiani. Penyaluran aspirasi tersebut hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengarah pada kekacauan, melainkan melalui saluran-saluran yang tepat, di antaranya adalah anggota jemaat yang menjadi kader partai politik ataupun menjadi anggota legislatif dan eksekutif, baik di tingkat lokal maupun nasional. 2. Gereja perlu melakukan pertemuan konsultatif secara berkala dengan anggota-anggota jemaatnya yang terlibat dalam politik praktis. Dikatakan “konsultatif”, karena dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak (gereja dan aktivis politik) dapat saling memberi masukan dan saling belajar. Dalam pertemuan tersebut gereja dapat menyuarakan suara kenabiannya, menyampaikan berbagai pertimbangan moraletisnya, tetapi sekaligus juga belajar dan mendapatkan informasi yang benar mengenai berbagai perkembangan politik yang ada. 3. Gereja perlu juga mendengar masukan dari berbagai LSM ataupun perguruan tinggi-perguruan tinggi Kristen yang menaruh perhatian terhadap kehidupan politik. Karena dari lembaga-lembaga inilah gereja akan mendapatkan berbagai masukan yang relatif obyektif. Lembaga-lembaga tersebut juga dapat berfungsi sebagai counter-opinion, sehingga gereja tidak hanya mendengar dari anggotanya yang memiliki jabatan di partainya atau di badan-badan legislatif dan eksekutif saja. 4. Gereja perlu menyelenggarakan berbagai pembinaan ataupun juga forum diskusi yang menggumuli masalah-masalah politik dan etikanya bagi anggota jemaatnya, sehingga pemahaman-pemahaman yang salah yang dimiliki oleh anggota jemaat tentang politik dapat diluruskan dan sekaligus dapat mendorong anggota jemaatnya ikut berperan dalam kehidupan politik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. 5. Gereja perlu terlibat dalam forum-forum dialog antar umat beragama. Karena dalam konteks Indonesia saat ini yang dihadapi oleh gereja bukanlah umat beragama lain, tetapi kelompok-kelompok ekstrim yang bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Kelompok ekstrim ini tidak hanya terdapat pada umat beragama yang lain, tetapi juga di kalangan umat Kristen sendiri. Keikut-sertaan gereja dalam dialog seperti ini akan mengamplifikasi suara Kristen di tengah-tengah percaturan politik lokal maupun nasional. Selain itu gereja juga menghadapi krisis kepribadian dan moral bangsa yang tidak mungkin ditangani oleh gereja sendirian. Seluruh kelompok agama mesti bersinergi untuk mendidik dan membangun kepribadian dan moral bangsa yang benar. Penutup Apa yang diuraikan di atas hanyalah merupakan suatu stimulan bagi kita semua. Saya berharap bahwa forum ini tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan dapat menjadi awal dari jemaat-jemaat untuk secara sadar mulai memberi perhatian terhadap perkembangan politik lokal maupun nasional. Dengan demikian Gereja dapat berperan serta – seminimal apapun – dalam kehidupan publik dan bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa yang lain memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 8 Daftar Kepustakaan Yohanes Calvin: Institutio, Pengajaran Agama Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985 DR. H. Berkhof & Dr. I.H. Enklaar: Sejarah Gereja, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987 Joseph Haroutunian: Piety vs Moralism, New York and Evanston: Harper Torchbook, Harper & Row, Publisher, Inc, 1970 Yahya Wijaya: Church-State-Market Relations in the Context of Indonesia, Asia Journal of Theology, 21:3, 2007 DR. Leo Suryadinata: Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta: Grafitipers, 1986 Koson Srisang: Perspectives on Political Ethics, an Ecumenical Enquiry, Switzerland: WCC Publishers, 1983 John Howard Yoder: The Politics of Jesus, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975 Merriam-Webster’s 11th Collegiate Dictionary, 3.0 version (CD format) http://en.wikipedia.org/wiki/Politic 9