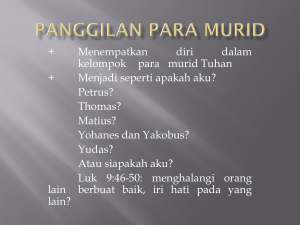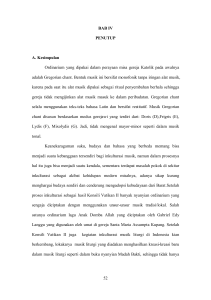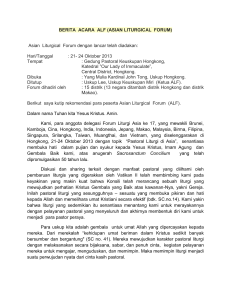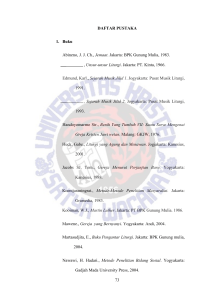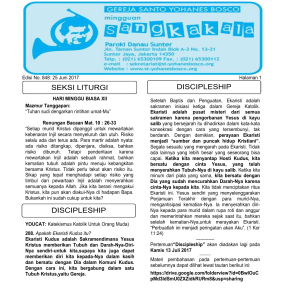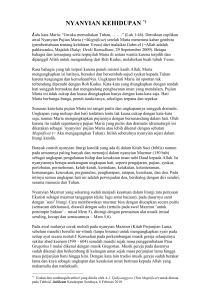Liturgi Gereja Kristen Jawa - Universitas Kristen Satya Wacana
advertisement
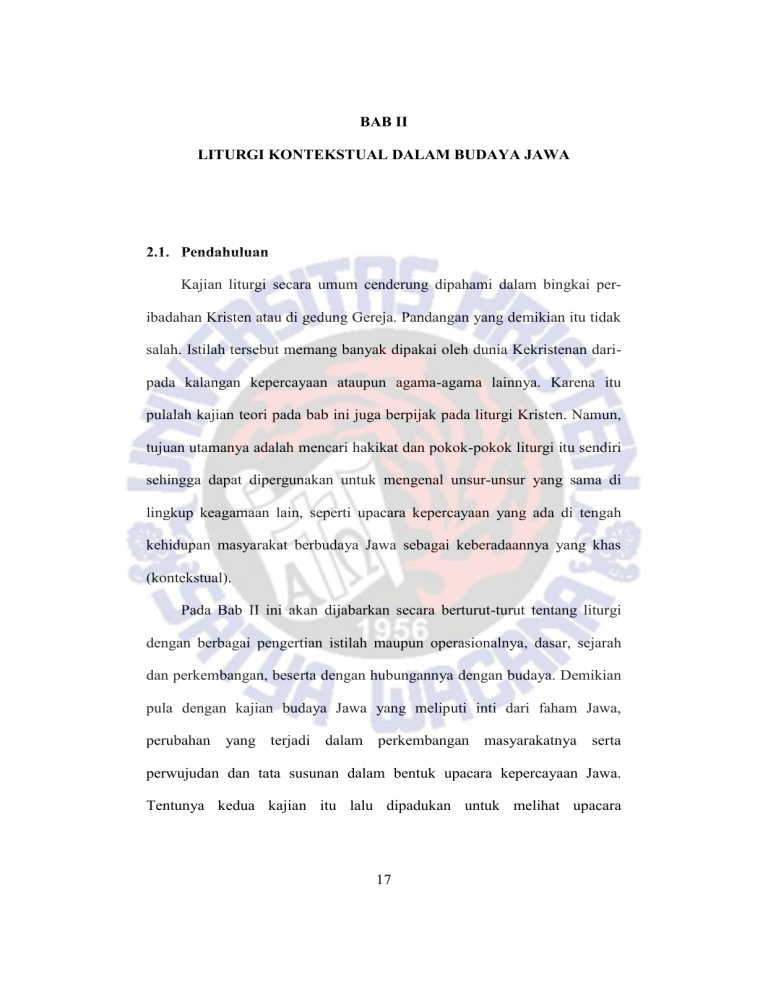
BAB II LITURGI KONTEKSTUAL DALAM BUDAYA JAWA 2.1. Pendahuluan Kajian liturgi secara umum cenderung dipahami dalam bingkai peribadahan Kristen atau di gedung Gereja. Pandangan yang demikian itu tidak salah. Istilah tersebut memang banyak dipakai oleh dunia Kekristenan daripada kalangan kepercayaan ataupun agama-agama lainnya. Karena itu pulalah kajian teori pada bab ini juga berpijak pada liturgi Kristen. Namun, tujuan utamanya adalah mencari hakikat dan pokok-pokok liturgi itu sendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mengenal unsur-unsur yang sama di lingkup keagamaan lain, seperti upacara kepercayaan yang ada di tengah kehidupan masyarakat berbudaya Jawa sebagai keberadaannya yang khas (kontekstual). Pada Bab II ini akan dijabarkan secara berturut-turut tentang liturgi dengan berbagai pengertian istilah maupun operasionalnya, dasar, sejarah dan perkembangan, beserta dengan hubungannya dengan budaya. Demikian pula dengan kajian budaya Jawa yang meliputi inti dari faham Jawa, perubahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakatnya serta perwujudan dan tata susunan dalam bentuk upacara kepercayaan Jawa. Tentunya kedua kajian itu lalu dipadukan untuk melihat upacara 17 kepercayaan Jawa sebagai liturgi, sekaligus liturgi yang kontekstual. Akhirnya, seluruh hasil kajian teori yang tersebut ditutup kesimpulan. 2.2. Liturgi 2.2.1. Arti Liturgi Seperti disinggung secara singkat pada Bab I, Brownlee menjelaskan bahwa liturgi merupakan kata dari bahasa Yunani, yaitu leitourgia (λειτουργία). Istilah itu nampak dalam Kitab Perjanjian Baru bersama dengan kata lain yang memiliki kemiripan arti, yaitu latreia (λατρεία). Arti harafiah kedua istilah tersebut adalah karya pengabdian atau karya bakti bagi kepentingan umat secara umum. Pada Kitab Perjanjian Lama kedua istilah itu dikenal dengan kata sharath ( ) שרתdan abodah ( ) ﬠבּידּה, yang diIndonesia-kan menjadi ibadah, dan artinya kebaktian atau pelayanan.22 Jadi menurut arti katanya, istilah liturgi dan ibadah tampaknya hampir tidak ada bedanya. Seperti dikatakan H. A. van Dop, arti keduanya seakan sama saja.23 Selain itu, meminjam sebutan dari Emanuel Martasudjita dan James F. White, bahwa istilah-istilah tersebut sesungguhnya merupakan pekerjaan bermakna sekular yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Liturgi maupun ibadah adalah tindakan yang dilakukan oleh umat tanpa pamrih demi kepentingan kota atau negara, sebagai pelayanan dan bakti.24 22 Brownlee, Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan, 19. H. A. van Dop, Hakikat dan Makna Liturgi, dalam: Liturgi dan Komunikasi (Jakarta, YAKOMA—PGI, 2005), 104. 24 James F. White, Pengantar Ibadah Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 13-14. 23 18 Misalnya memberi sumbangan, iuran, pajak, dan lain sebagainya. Karena itu secara teologis hakikat liturgi di dalam Kekristenan yang didasarkan pada peringatan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan tidak terpisahkan dengan peribadahan pada hari-hari kerja atau hari-hari biasa lainnya. Sebagaimana dikatakan J. L. Ch. Abineno bahwa pada dasarnya semula tidak ada batas jelas antara ibadah dan kehidupan sehari-hari Jemaat Mula-Mula. Sebab di antara keduanya memiliki hubungan yang cair dan fleksibel.25 Menurut kajian etimologis di dalam sejarah Gereja, arti liturgi maupun ibadah memiliki banyak istilah dan perkembangan arti. Selain empat istilah yang telah disebut, ada beberapa istilah lain yang biasa digunakan oleh Gereja. Pertama, worship (Inggris) yang berasal dari kata weorthscipe, artinya perbuatan yang baik atau yang layak dilakukan. Kedua, service yang berasal dari kata servitium (Latin), artinya pelayanan pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Ketiga, office yang berasal dari kata officium (Latin), artinya kesediaan untuk melayani. Keempat, cult/cultus yang berasal dari kata colere (Latin), artinya tindakan memberi (persembahan) yang menimbulkan ketergantungan atau ikatan hubungan antara pemberi dan penerima. Kelima, kebaktian yang berasal dari kata bakthi (Sansekerta), artinya perbuatan yang menyatakan setia melayani dan hormat, menghamba, serta perbuatan baik dengan kerelaan. Keenam, missa (Latin), yang merupakan penyingkatan dari kata “ite missa est!” dengan arti “inilah pembubaran 25 J. L. Ch. Abineno, Jemaat: Ujud, Peraturan, Susunan, Pelayanan, PelayanPelayannya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 72-73. 19 atau pengutusan”.26 Ketujuh, ritus (Latin), artinya peribadahan yang dilakukan sesuai dengan pola dan tata cara tertentu dalam petunjuk-petunjuk baku dan resmi bagi umat untuk pelaksanaan ekaristi, pelayanan-pelayanan pastoral maupun upacara-upacara peresmian. Dari istilah terakhir inilah kemudian muncul istilah kedelapan dan kesembilan, yaitu ceremony dan order yang menunjuk pada tata ibadah. Sebutan ceremony cenderung untuk pelaksanaan upacara peresmian, sedangkan order digunakan untuk urutan yang tersusun pada peribadahan.27 Kajian asal-usul istilah di atas memberikan pemahaman penting. Liturgi memiliki tiga arti mendasar yang sejajar, yaitu pelayanan, persembahan, serta perutusan.28 Ketiganya merupakan motivasi penting serta saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan peribadahan yang dilakukan dan sekaligus dirayakan oleh Gereja dari waktu ke waktu.29 Selanjutnya, meskipun secara harafiah memiliki pengertian umum yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, akan tetapi liturgi maupun peribadahan juga memiliki keterkaitan arti dengan kegiatan-kegiatan Gereja sebagai kebersamaan umat secara terbatas. Karena itu, pada satu segi tampaknya liturgi bisa dikatakan tidak sama persis dengan ibadah. Liturgi mengesankan sebagai suatu bentuk rumusan gagasan Gereja melalui tindakan di dalam pola dan tata cara yang tersusun secara teratur untuk mengungkapkan maksud ataupun tujuan tertentu di tengah 26 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 1-5 White, Pengantar Ibadah Kristen, 18-19. 28 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 6. 29 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 6-7. 27 20 keberadaan hidupnya. Adapun ibadah cenderung merupakan istilah bagi kegiatan umat secara umum, sebagaimana layaknya dilakukan juga oleh khalayak orang. Dengan kata lain, liturgi menjadi semacam tindakan teknis bagi penghayatan dari ibadah itu sendiri. Pembedaan itu makin tegas dengan adanya perkembangan makna dalam pemakaian masing-masing istilah di antara keduanya pada ranah lapangan penerapan. Liturgi cenderung digunakan untuk tata cara resmi ataupun upacara agung, sebagaimana terdapat dalam praktik keagamaan Gereja Katholik Roma. Adapun ibadah cenderung digunakan secara umum untuk menunjuk praktik keagamaan apapun, bahkan untuk kepercayaan-kepercayaan adat masyarakat suku.30 Ada tiga pendekatan untuk melihat pembedaan di atas. Pendekatan pertama adalah sudut arti kata. Dibandingkan dengan liturgi, ibadah dipandang lebih bermakna luas, cenderung praktis dan umum, tanpa harus ada pemaknaan khusus. Misalnya berderma, saling hormat, saling menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan wujud liturgi cenderung memiliki penghayatan khusus terkait dengan iman. Pendekatan kedua berpangkal pada makna teologis, di mana liturgi memiliki pengertian yang lebih luas dari pada ibadah yang gerakannya cenderung hanya searah dari tindakan umat kepada Tuhan (anabatis). Kelebihan liturgi dibandingkan dengan ibadah secara teologis, yaitu memiliki dua arah sebagai dialog. Selain anabatis, di dalam liturgi sekaligus juga terdapat katabatis, yaitu tindakan dari Tuhan kepada umat. Pendekatan ketiga adalah dimensi 30 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 4-5. 21 tindakan ibadah yang masih bisa bersifat pribadi dan tidak memiliki unsur resmi, sementara liturgi pasti merupakan tindakan bersama oleh umat dan resmi.31 Karena itu kaidah dasar pelaksanaan liturgi di dalam peribadahan tidak hanya terbatas pada kegiatan upacara keagamaan atau perayaan bagi Tuhan semata, tetapi juga merupakan sikap hidup sebagai pelayanan kepada Tuhan dengan bersedia tunduk dan hormat dalam tindakan, perilaku, kepribadian, maupun pemikiran dari segenap kehidupan umat.32 Pemahaman penting selanjutnya adalah bahwa istlah-istilah tata peribadahan Gereja beserta dengan makna dan penggunaannya di atas merupakan hasil penyesuaian budaya yang dilakukan Kekristenan dalam ruang persebaran dan perkembangannya. Semua kata sebutan itu digunakan oleh Gereja dalam rangka mengakarkan, sekaligus untuk mengungkapkan gagasan-gagasan imannya menurut konteks di tempat dia hidup. Pelayanan, persembahan, dan perutusan yang ada pada tindakan kemasyarakatan pada umumnya ternyata dipakai juga oleh Gereja sebagai liturgi untuk beribadah kepada Kristus Tuhan. Selangkah maju terhadap pemahaman umum maupun khusus tersebut, memperlihatkan adanya penalaran bahwa adat-istiadat yang terangkai dengan berbagai wujud ritual kepercayaan bagi kebersamaan oleh suatu masyarakat memungkinkan untuk dipakai Gereja melalui langkah tertentu sebagai liturgi peribadahan. Kemungkinan itu dimiliki pula oleh GKJ di tengah budaya masyarakatnya. 31 E. Martasudjita, Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 26-30. 32 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 4. 22 2.2.2. Definisi Liturgi Kajian etimologi di atas menjadi dasar pemahaman makna liturgi menurut sudut-sudut batasan operasional atau definisi yang ditekankan. Ada empat sudut penekanan dalam mendefinisikan liturgi, yaitu dari sudut aksi, sudut dasar aksi, sudut isi gagasan, dan sudut ruang penghayatan. Berdasarkan sudut aksi, liturgi didefinisikan sebagai kegiatan ibadah, baik berbentuk seremonial maupun praksis. Maksud ibadah praksis adalah seperti yang diungkapkan oleh Rasid, yaitu ibadah yang tidak terbatas pada perayaan di gedung Gereja melalui selebrasi, tetapi terwujud pula di dalam sikap hidup orang percaya di dunia sehari-hari melalui aksi yang meliputi pelayanan, tindakan, tingkah laku, hidup keagamaan, spiritualitas, praksis hidup, pola maupun cara berpikir, menanggapi, dan sebagainya.33 Karena itu, pada diri liturgi mesti terdapat keikutsertaan umat secara bersungguhsungguh untuk ikut ambil bagian, sebagai ungkapan hidup imannya.34 Dari sudut dasar aksi, liturgi didefinisikan sebagai kehidupan Kristen yang diungkapkan sebagai ibadah untuk menyatakan penyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus, sekaligus merupakan tanggapan manusia terhadapnya.35 Intinya adalah bahwa di dalam ibadah Allah bertindak untuk memberikan hidupNya bagi manusia serta membawa manusia untuk ikut mengambil bagian di dalam kehidupan. Karena itu, semua yang dilakukan oleh umat selaku pribadi ataupun Gereja dipengaruhi oleh ibadah. 33 34 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 1. Bosco Da Cunha, Teologi Liturgi dalam Hidup Gereja (Malang: Dioma, 2004), 1- 2. 35 White, Pengantar Ibadah Kristen, 7. 23 Adapun menurut sudut isi gagasannya liturgi didefinisikan sebagai pertemuan umat di hadapan Allah, bahkan dengan Allah sendiri. Karena itu liturgi peribadahan bukanlah tata cara atau bentuknya melainkan isinya, yaitu umat bersama dengan segala sesuatu yang dilakukan di dalam perkumpulannya bermakna untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia di hadapanNya dan di dalam namaNya.36 Ketiga definisi di atas memperlihatkan ada nisbah yang bisa dipadukan. Pertama, bila liturgi pada definisi pertama dipandang sebagai kegiatan pengungkapan iman Gereja oleh keikutsertaan umat yang mendorong perwujudan nyata dalam segenap bidang kehidupan maka definisi liturgi yang kedua dapat dipandang sebagai penyebab tindakan Gereja itu sendiri, yaitu penyataan Allah yang memberikan hidupNya bagi manusia. Karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam definisi liturgi yang kedua, maka kegiatan pengungkapan iman Gereja merupakan tanggapan terhadap penyataan Allah itu. Kedua, perpaduan definisi liturgi yang pertama dan kedua tersebut menunjukkan adanya prakarsa di antara pihak Allah dan manusia menjadi suatu perjumpaan yang disebut pada definisi liturgi yang ketiga sebagai makna bagi umat untuk melayani Allah maupun sesama menurut iman. Berikutnya berdasarkan sudut ruang penghayatan, liturgi didefinisikan sebagai tempat bagi umat menyanyikan akan pengharapan dan masa depan. Liturgi adalah wahana yang di dalamnya umat terhanyut oleh visi 36 van Dop, Liturgi dan Komunikasi, 104-107. 24 kedatangan Kerajaan Allah dengan pelayanan kepada Allah dan sesama.37 Sudut definisi liturgi yang terakhir ini memperlihatkan kedudukan pelayanan yang dilakukan umat bukan sekedar kegiatan Gereja beserta penyebab, ataupun isi gagasannya. Keberadaan liturgi dari sudut ruang penghayatan tersebut cenderung memahami pelayanan sebagai arena sekaligus wujud penghayatan akan tujuan dari iman yang diungkapkan oleh Gereja. Penekanan-penekanan dari keempat definisi liturgi di atas nampaknya sekaligus menjadi cara pendekatan masing-masing. Namun keragaman penekanan maupun cara pendekatan beberapa definisi liturgi tersebut bila dipadukan memungkinkan memberikan pengertian yang utuh, yaitu perjumpaan umat bersama dengan Allah sebagai tanggapan sekaligus penghayatan atas penyataan Allah yang telah memberikan hidupNya untuk keselamatan manusia berupa pelayanan seremonial maupun praksis. 2.2.3. Dasar Liturgi Secara langsung ataupun tidak langsung, etimologi dan definisi liturgi di atas menunjukkan adanya dasar-dasar penting yang berpusat pada soal tafsir, sejarah, budaya maupun adat-istiadat, dan penyesuaian terkait iman di dalam kemunculan serta perkembangan Kekristenan. Artinya, tata peribadahan di dalam Kekristenan dibangun dengan memberi makna atas peristiwa 37 atau pengalaman nyata, dan perwujudannya dilakukan E. H. van Olst, Alkitab dan Liturgi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 111. 25 penyesuaian atas tata kebiasaan dan tradisi dalam budaya yang terdapat pada kehidupan bersama suatu masyarakat. Dari sebuah kajian teologi terhadap liturgi terungkap bahwa kemunculan liturgi Kristen atau Gereja berawal dari langkah hermeneutik baru melalui Yesus yang disebut Kristus dan Tuhan atas peribadahan masyarakatNya, yang tumbuh berakar dari kebudayaan Yahudi. Oleh Yesus itu, sekelompok orang Yahudi yang bercaya kepadaNya menafsirkan ulang ketidakpastian perkembangan keadaan kemasyarakatan beserta keagamaan masa itu yang sulit menemukan sarana peribadahan sebagai alat peneguhan umat karena akhirnya hancur di masa penjajahan bangsa Roma.38 Sarana peribadahan yang kemudian hilang dari budaya dan adat-istiadat ibadah keagamaan Yahudi itu berupa kenisah, altar, dan korban. Selain menjadi perangkat peneguhan bagi keutuhan umat, sarana-sarana tersebut juga merupakan pemujaan, penyembahan, serta penyucian umat kepada Allah yang melambangkan penyelamatan. Pada sosok Yesus semua budaya keagamaan yang musnah dalam sejarah politik bangsa Yahudi itu dicerminkan kembali.39 Artinya, seperti penjelasan Brox40 dan Everett Ferguson41 bahwa sarana-sarana peribadahan Yahudi sebagaimana ada pada tradisi Kitab Perjanjian Lama telah disatukan dan dibangun kembali dalam figur Yesus. Yesus diyakini umat sebagai pribadi Messias melalui 38 R. S.Sugirtharajah, Poscolonial Criticism and Biblical Interpretation (New York: Oxford University Press, 2002), 91. 39 Bosco Da Cunha, Teologi Liturgi dalam Hidup Gereja, 29-33. 40 Brox, A History of the Early Church, 2-4. 41 Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity ((Michigan: Grand Rapids, 1994), 517-519. 26 penafsiran baru atas tradisi keagamaan dalam kitab-kitab Ibrani maupun sejarah perubahan yang telah terjadi di tengah masyarakatnya, dan kemudian dijadikan tradisi baru atau tradisi pengganti.42 Sepanjang keberadaan liturgi, dasar-dasar penting yang disebutkan di atas juga ada. Langkah pembaruan yang terjadi pada peristiwa Yesus itu terlihat pula pada tradisi-tradisi penerusnya, yaitu tradisi apostolik43 dan tradisi reformasi Gereja.44 Pada tradisi apostolik unsur-unsur mendasar ditemukan dalam tiga titik tolak, yaitu sejarah liturgi Gereja, sejarah tempat dan waktu pelaksanaan liturgi Gereja, serta sejarah perayaan liturgi oleh Gereja Perdana. Di dalam sejarah liturgi Gereja, kesadaran iman akan Yesus yang hidup dan bangkit dari kematian mengubah cara hidup Gereja, khususnya penafsiran peribadahan. Pengabsahan ibadah yang semula bersifat lahiriah berupa kenisah, altar, dan korban di Bait Allah berganti yang rohaniah melalui Yesus Kristus untuk memuji, menyembah, dan menguduskan umat kepada Allah dengan dalil “dalam roh dan kebenaran” oleh kesediaan dipimpin Roh Kudus. Sementara di dalam sejarah tempat dan waktu pelaksanaan, peribadahan Gereja yang sempat dilakukan oleh Jemaat MulaMula mengikuti tradisi pada hari Sabat di Bait Allah berangsur diubah di rumah-rumah secara bergantian pada hari Akhad atau yang dikemudian 42 Richard E. Palmer, Hermuneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 39-42. 43 Brox, A History of the Early Church, 4-5. 44 Arlo D. Duba, W. B. Sidjabat, Asas-Asas Kebaktian Alkitabiah dan Protestan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), 23-39. 27 waktu disebut pula hari Minggu,45 yaitu hari peringatan akan Yesus yang hidup dan bangkit dari kematian. Adapun di dalam sejarah perayaan liturgi oleh Gereja Perdana, pada tradisi hari peribadahan yang baru itu selalu dilakukan pengajaran para rasul, berdoa bersama, serta makan bersama (perjamuan agape) maupun memecah-mecahkan roti sebagai perjamuan Tuhan (ekaristi) untuk mengenang (anamnese) akan pengalaman penyelamatan Allah pada umat, seperti mandat Yesus sendiri dalam Perjamuan Malam Paskah menurut tradisi keagamaan Yahudi.46 Pada tradisi reformasi Gereja dasar-dasar penting liturgi di atas terungkap, khususnya dalam tafsiran teologis atas perkembangan Gereja di tengah kehidupan politik yang meliputi delapan hal. Pertama adalah dalil sola scriptura, sehingga sebagai firman Allah maka Alkitab memiliki otoritas tertinggi di dalam peribadahan Kristen sekaligus merupakan dokumen liturgis. Kedua adalah Allah Maha Kuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan umat, sehingga di dalam peribadahan umat tidak bisa berliturgi semena-mena menurut pikiran, keinginan, dan kesenangannya sendiri. Umat harus bersedia tunduk dan berserah kepada seluruh kehendak yang difirmankan Allah (epiklese). Ketiga adalah norma praktik apostolik, sehingga liturgi pribadahan Kristen mesti mengacu sekaligus memiliki kesesuaian dengan praktik-praktik dari Jemaat Mula-Mula sewaktu para rasul mengajar. Keempat adalah pemulihan makna penggunaan waktu secara tepat, sehingga semua hari dalam seminggu berhubungan dengan sejarah penyelamatan 45 46 Martasudjita, Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi, 51. Brox, A History of the Early Church, 92-93, 100-101. 28 Allah bagi umat. Karena itu peringatan yang dilakukan tiap hari Minggu dalam liturgi peribadahan merupakan tindakan umat untuk mengenang penyelamatan Allah (anamnese). Kelima adalah firman dan perjamuan kudus sebagai kebaktian normatif, sehingga ibadah sebagai anamnese tidak bisa mengurangi, menggantikan, bahkan menghilangkan kedua unsur itu. Keenam adalah bahwa kebaktian sebagai peristiwa persekutuan, sehingga Gereja tidak bisa menjadi lembaga statis. Gereja harus in transitius, yaitu lembaga yang bergerak atau hidup dari umat yang mengadakan perziarahan. Ketujuh adalah pemulihan partisipasi umat, sehingga tata peribadahan tidak berpusat pada satu pelayan melainkan seluruh umat yang saling melayani sebagai peristiwa persekutuan dalam satu tubuh Kristus dengan keteraturan dan penuh rasa hormat. Kedelapan adalah norma pastoral. Artinya sejauh manakah pengertian dari dasar tata peribadahan yang pertama sampai ketujuh di atas dapat diterapkan atau dikontekstualisasikan dalam keberadaan umat sehingga tujuannya tercapai oleh umat. Karena itu pelaksanaan liturgi di dalam peribadahan perlu per-timbangan pastoral berdasarkan persoalan yang ada di tengah kebersamaan umat itu.47 2.2.4. Sejarah dan Perkembangan Liturgi Kedua tradisi di atas menguatkan keterkaitan tafsir, sejarah, budaya beserta tradisi suatu masyarakat, sebagai dasar keberadaan liturgi Kristen yang secara lebih jelas sangat kelihatan pada historisitas dan per47 Arlo D. Duba, W. B. Sidjabat, Asas-Asas Kebaktian Alkitabiah dan Protestan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), 23-39. 29 kembangannya. Pertama kali muncul umat Kristen, liturgi peribadahan dalam bentuk rumusan khusus dan baku pada dasarnya belum ada. Liturgi dalam peribadahan Kristen Perdana sesungguhnya mengalir mengikuti kebiasaan yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat sebelumnya, yaitu tradisi peribadahan Yahudi yang memiliki konteks keberagamaan atau keimanannya sendiri.48 Dari berbagai konteks keagamaan masyarakat Yahudi itu sendiri, tampaknya ada tradisi umum dan tradisi khusus yang menjadi sumber penting dalam kemunculan peribadahan Kristen, yaitu Paskah dan Baptisan. Paskah merupakan tradisi keagamaan yang umum bagi masyarakat Yahudi, sedangkan Baptisan merupakan tradisi keagamaan khusus yang hanya dimiliki dan dilakukan oleh golongan tertentu dalam masyarakat Yahudi itu. Dalam suatu kajian, baptisan merupakan ritual yang berasal dari kaum Esseni untuk orang yang dibaiat sebagai anggota. Sejauh mana hubungannya dengan tradisi yang terdapat pada Kitab Perjanjian Lama, yang pasti baptisan yang mereka lakukan itu sebagai lambang dari kesucian atau kemurnian hidup yang menjadi cita-cita dan gerakan mereka di tengah keprihatinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya kala itu. Karenanya, meski belum bisa di-anggap bagian dari kaum Esseni, dimungkinkan Yesus (demikian pula Yohanes Pembaptis) memiliki hubungan dengan kaum Esseni. Sebab dari kehidupan dan karyaNya memperlihatkan kemiripan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kaum itu. 48 Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 503-527. 30 Selain baptisan, mereka sangat kuat dalam ritual-ritual kesucian, anti kekerasan, serta selalu melakukan propaganda tentang Kerajaan Allah dan pertobatan.49 Pandangan mengenai asal-usul tradisi baptisan tersebut bertentangan dengan kajian lain yang menganggap berasal dari tradisi Rabbinik. Menurut pandangan Rabbinik, baptisan yang dijalani setelah sunat adalah untuk menjadikan seseorang sebagai bagian dari Umat Perjanjian, seperti pengalaman yang terjadi pada diri Yesus. Tradisi itu kemudian menjadi lebih khas di dalam perkembangan Kekristenan sebagai pandangan sektarian yang jauh terbuka dan mendalam dengan tidak membatasi pada kalangan Yahudi saja seperti kaum Esseni, ataupun menjadikan seseorang menjadi Yahudi seperti kaum Rabbinik, tetapi bagi semua orang tanpa melihat syarat asal-usulnya maupun sunat atau tidak sunat.50 Dan itulah sebabnya, baptisan juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan Yesus, dan akhirnya diikuti oleh para murid atau para pengikutNya. Meskipun berbeda, kedua pandangan asal-usul baptisan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pada mulanya baptisan sendiri sesungguhnya merupakan hasil tafsir kelompok-kelompok masyarakat Yahudi yang mampu mereka terima dan menjadi sebuah tradisi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu sebagai tanda pengenal sekaligus lambang gagasan cita-cita iman kemasyarakatan mendasar di tengah keprihatinan atas perubahan 49 John Stambaugh dan David Balch, Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 91-124. 50 Justin Taylor, Asal-Usul Agama Kristen (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 142-150. 31 kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang mereka miliki. Sehubungan dengan baptisan di dalam Kekristenan, pada intinya juga memiliki dasardasar bangunan penting yang sama. Namun sifat gerakan yang dilambangkan dengan baptisan Kristen bertolak belakang dengan kaum Esseni maupun Rabbinik. Bila pandangan baptisan mereka terbatas bagi tujuan kelompok atau bangsa mereka sendiri, maka baptisan pada Kekristenan lebih terbuka bagi semua golongan, masyarakat, maupun bangsa. Dalam perkembangannya, tradisi Paskah maupun tradisi Baptisan itu selanjutnya menjadi sumber penting bagi ibadah maupun liturgi umat Kristen, yang secara mengesankan ditumbuhkan oleh peristiwa yang dijalani Yesus, mulai dari Perjamuan Malam menjelang hari Paskah, kematianNya di hari Paskah, maupun kebangkitanNya di hari pertama setelah hari Sabbath, yaitu hari Akhad. Peristiwa pada hari Akhad itu selalu dijadikan anamnese bagi umat Kristen dengan perjamuan agape maupun ekaristi serta baptisan. Selain kedua tradisi penting di atas, ada kebiasaan-kebiasaan dari peribadahan Yahudi yang juga diikuti dalam liturgi Kristen.51 Kebiasaan itu adalah melantunkan Kitab Mazmur, membaca Kitab Suci (Taurat dan NabiNabi) seperti di Sinagoge dengan diikuti khotbah pengajaran dari para rasul, dan pada waktu kemudian ditambah dengan membaca Epistel dan Injil, yang kemudian diakhiri dengan doa bersama.52 Tata urutan peribadahan untuk mengenang Yesus secara sederhana itu dikenal juga dengan sebutan 51 52 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 13-14. Brox, A History of the Early Church, 4-5. 32 liturgi synaxis, yaitu liturgi persekutuan untuk membaca Kitab Suci, menyanyikan Mazmur, serta berdoa bersama di Sinagoge.53 Namun, yang membedakan antara liturgi umat Kristen dengan umat Yahudi itu adalah adanya perjamuan agape, ekaristi, dan baptisan. Berpijak dari tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan di atas itulah liturgi peribadahan umat Kristen terbentuk dan berkembang. Meskipun pada perkembangan masa dan tempat persebaran umat Kristen di luar daerah bangsa Yahudi begitu pesat dan memiliki keanekaragaman yang khas karena perjumpaan dengan budaya masyarakat yang baru beserta dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, namun inti liturgi yang memiliki ciri-ciri warisan dari tata tradisi keagamaan orang Yahudi tetap dipertahankan dan dijadikan isi pokok peribadahan Kristen. Ini dapat dilihat dalam periode umum perkembangan Gereja dari masa awal hingga sekarang. Periode pertama yaitu masa Gereja Perdana. Gereja yang dipimpin oleh para rasul Yesus Kristus ini melakukan baptisan dan perjamuan dengan spontan di rumah-rumah mereka secara bergiliran yang disertai dengan pem-bacaan Kitab Suci dan khotbah pengajaran, menyanyikan puji-pujian, dan berdoa bersama-sama, seperti liturgi persekutuan di Sinagoge dan dilakukan pula oleh Yesus sendiri.54 Liturgi Gereja Perdana tersebut awalnya berjalan tanpa terikat pada tatanan, tulisan, maupun aturan liturgi tertentu. Di masing-masing daerah memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. 53 54 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 15. Matius 4:23, Markus 6:2, Lukas 4:16, Yohanes 6:59 LAI. 33 Ada yang biasa seperti umat Kristen di Yerusalem, namun ada yang kreatif dalam keikutsertaan umat secara aktif di dalam peribadahan seperti umat Kristen di Korintus.55 Periode kedua adalah masa Gereja Patriarkhi. Masa ini dikenal juga sebagai masa para Bapa Gereja, yaitu para pemimpin umat Kristen yang menjadi penerus Rasul-Rasul Yesus Kristus. Pada masa ini terdapat dua tahap perkembangan yang mewarnai liturgi dalam peribadahan umat Kristen. Tahap pertama adalah kehidupan yang sulit. Gereja tidak hanya menghadapi penolakan yang semakin besar dari masyarakat asalnya tetapi juga mendapat tekanan politis yang sangat keras dari penguasa Romawi, maupun pemurtadan dari berbagai kalangan keagamaan yang hidup pada waktu itu.56 Karena itu, di dalam konteks masa awal tersebut tata peribadahan umat Kristen bersifat pastoral. Untuk menghadapi tekanan masyarakat dan agama yang ada di sekitarnya, maupun penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa Romawi, maka Gereja memiliki Didache, Apologia, ataupun Apostolike Paradosis (Apostolic Tradition) sebagai tulisan yang digunakan di dalam peribadatan. Tulisan-tulisan yang digunakan di dalam peribadatan tersebut sudah menampakkan adanya tata urutan yang tersusun.57 Kebenaran dari keadaan liturgi pada masa Bapa-Bapa Gereja awal itu dapat dilihat dalam terjemahan tata peribadahan mereka yang dihimpun oleh Bard Thompson. Pada tulisan55 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 17. Th. van Den End, Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Singkat (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 34-56. 57 Martasudjita, Liturgi, 53-55. 56 34 tulisan itu ditemukan bahwa sebelum diadakan ekaristi, terlebih dulu dilakukan pembacaan Kitab Suci dan khotbah atau pengajaran-pengajaran yang berasal dari para rasul. Sesudah itu dilanjutkan dengan doa oleh umat yang disusul dengan pengucapan syukur atas roti dan anggur maupun air bagi ekaristi untuk dibagikan kepada umat. Demikian pula dengan pelaksanaan baptisan yang dilakukan di tengah peribadahan umat.58 Kesulitan pada masa Bapa-Bapa Gereja awal di atas mengalami perkembangan sebagai tahap kedua, yaitu kehidupan yang terbuka di bawah pengaruh politik kekuasaan pemerintah Romawi. Dengan pamrih dapat memanfaatkan kesetiaan orang-orang Kristen pada imannya untuk memperkuat kesatuan negara, maka pada jaman Kaisar Konstantinus dikeluarkan edik di Milan untuk menghentikan penindasan terhadap orang-orang Kristen yang sulit ditekan dan malah cenderung berkembang. Sejak itu Kekristenan diijinkan tumbuh bebas di kekaisasan Romawi.59 Bahkan pada masa berikutnya, untuk mengukuhkan tujuan politik tersebut Kaisar Gratianus dan Kaisar Teodosius menjadikan Kekristenan sebagai agama negara.60 Tahap perubahan kedua dalam periode perkembangan Gereja ini, berdampak besar pada kehidupan Gereja, khususnya pada peribadahan umat yang keadaan dan suasananya sangat berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Ketika Kekristenan masih ditolak dan ditindas, pelaksanaan liturgi peribadahan umat Kristen penuh dengan suasana kekeluargaan dan sederhana di rumah58 Bard Thompson, Liturgies of the Western Church (Philadelphia: Fortress Press, 1982), 4-9. 59 van Den End, Harta dalam Bejana, 57. 60 Martasudjita, Liturgi, 56-57. 35 rumah, bahkan di katakombe-katakombe, atau tempat-tempat tersembunyi lainnya. Namun, semenjak diperbolehkan dan akhirnya dijadikan agama resmi negara, Kekristenan diistimewakan dengan gelar kebangsawanan ataupun pengangkatan sebagai pejabat negara istimewa bagi para imam Gereja, bahkan memberikan kedudukan sebagai masyarakat kelas utama bagi umat Kristen.61 Dampak lain pemberian tempat dan kedudukan Kekristenan di tengah masya-rakat yang demikian itu mengubah citra peribadahan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana lengkap dari negara. Pelaksanaan peribadahan menjadi penuh dengan suasana resmi, hirarkis, serta kemegahan dan mewah ala imperial basilika. Bahkan, di masa itu mulai muncul liturgi-liturgi untuk aneka tujuan atau keperluan. Misalnya liturgi peneguhan dan pelantikan para petinggi atau para pejabat negara, terlebih para pejabat gerejawi yang dengan sendirinya menjadi pejabat negara, pernikahan, dan lain sebagainya.62 Pola-pola liturgi yang berkembang di dalam peribadahan Kristen pada masa Gereja Patriarkhi tersebut memiliki penekanan ritual sebagai pendekatan terhadap berbagai perubahan di dalam tata kehidupan baru dan keagamaan masyarakat Roma waktu itu. Namun demikian, liturgi peribadahan utama yang dilakukan pada tiap hari Minggu dengan inti pengajaran dan sakramen perjamuan masih tetap memiliki pola kecenderungan dasar yang sama. Ada doa syukur umat yang dilanjutkan dengan pembacaan Kitab-Kitab Suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian 61 62 Martasudjita, Liturgi, 56-57. Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 57-63. 36 Baru dengan selingan lantunan nyanyian pujian ataupun mazmur sebelum pengajaran dan doa pengucapan syukur untuk sakramen perjamuan. Hanya saja, yang membedakan dengan masa sebelumnya adalah peran serta umat dalam liturgi yang berangsur kurang dibandingkan dengan peran serta kaum imam yang semakin besar dan menentukan di dalam segala hal.63 Keadaan perkembangan liturgi di atas terus berlanjut pada periode perkembangan yang ketiga, yaitu masa Gereja Abad-Abad Pertengahan. Pada periode ini terjadi perubahan besar, yaitu kekuasaan politik Romawi Barat yang kian surut dan berangsur cepat beralih ke tangan Gereja. Perubahan itu ditandai dengan kemunculan Papal (Paus) sebagai pemimpin Gereja tertinggi di wilayah Romawi Barat yang memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam kehidupan umat Kristen maupun masyarakat.64 Pengaruh dari Paus tersebut nampak dalam kehidupan peribadahan umat dengan banyaknya pemberlakuan Ritus Roma atau Liturgi Roma (yang sekarang dikenal dengan Liturgi Gereja Katholik) pada Gereja di lingkup kekuasaannya.65 Namun pemberlakuan liturgi tersebut tidak sepenuhnya memiliki alasan politis. Semenjak Kekristenan mengalami kebebasan maka akibat yang kurang menguntungkan adalah banyaknya percobaan-percobaan liturgi yang dilakukan oleh para uskup maupun abbas sehingga memunculkan ketidakpuasan dan kebingungan umat terhadap pelaksanaan liturgi.66 63 van Olst, Alkitab dan Liturgi, 88-91. Christiaan de Jonge, Pembimbing ke dalam Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987), 60-70. 65 Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 77. 66 Martasudjita, Liturgi, 70. 64 37 Apapun penyebab kuatnya pengaruh Liturgi Roma yang kian menyebar di tengah bangsa-bangsa daerah Romawi Barat pada masa perkembangan Gereja Abad Pertengahan tersebut, yang pasti di dalam pelaksanaannya nampak ada suasana resmi dan begitu rumit, bahkan khas dengan bahasa pengantar, yaitu Latin. Selain itu, peran imam menjadi menonjol dan meng-geser kedudukan umat,67 sehingga terkesan menjadi penentu peribadahan. Karena itu Ritus Roma disebut juga dengan Liturgi Klerus. Dengan penggunaan pola yang serba resmi menurut peran para imam tersebut, umat semakin terasing dari liturgi karena bahasa pengantarnya maupun pokok-pokok yang ada di dalam tata susunan liturgi hampir semua dikuasai dan diperankan oleh para imam dengan rumusan baku, terutama dengan doa.68 Bahkan, di dalam liturgi itu sendiri juga memiliki pemahaman iman tentang keselamatan yang banyak berkembang secara berjenjang,69 apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Keselamatan yang diimani umat terkesan lebih terjamin melalui roh-roh para tokoh perantara yang dipandang suci dan mampu menolong (santo dan santa) untuk memperoleh pengampunan dan pengudusan dari Tuhan. Pergeseran ataupun perkembangan tersebut dimungkinkan juga berimbas pada pemahaman dan tata perlakuan atas lambang-lambang di dalam peribadahan. Roti dan anggur setelah penyucian dengan doa syukur dan berkat serta pengucapan kata-kata 67 Thompson, Liturgies of the Western Church, 54-91. Martasudjita, Liturgi, 72. 69 Thompson, Liturgies of the Western Church, 54-91. 68 38 yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus sewaktu Perjamuan Malam Paskah oleh imam diyakini telah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri (hosti). Karena itu, cara penerimaannya tidak boleh sembarangan dan harus dengan penuh rasa hormat. Hosti harus diletakkan oleh imam secara langsung pada lidah tiap umat yang berhak menerimanya. Demikian pula dengan altar, Kitab Suci, bejana roti dan anggur, salib, rosary, hingga para santo dan santa dengan relik-relik mereka yang dipandang memiliki daya pengaruh oleh ritual yang dilakukan oleh para imam Gereja.70 Semua itu memberi kesan kecenderungan untuk memberikan makna keselamatan umat ditentukan atau diukur oleh tindakan Gereja melalui ritus;71 sehingga di luar Gereja tidak ada keselamatan (extra ecclesiam nulla salus). Pentingnya ritus di dalam peribadahan itu sekaligus menunjukkan pula adanya kuasa kaum imam Gereja yang sangat menentukan bagi keselamatan umat.72 Puncak kecenderungan-kecenderungan peribadahan semacam itu menjebak Gereja dalam sekularisme yang terungkap dengan peristiwa penerbitan surat penghapusan siksa (indulgensi).73 Sekularisme di tengah Gereja itulah yang mencetuskan periode sejarah berikutnya, yaitu periode masa Reformasi Gereja.74 Pada periode perkembangan Gereja yang keempat ini umat mengadakan perlawanan terhadap sekularisme yang menyebabkan kesewenang-wenangan para imam 70 van Den End, Harta dalam Bejana, 141-142. Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 135. 72 H. Berkhof, I. H. Enklaar, Sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 71 111. 73 74 Berkhof, Enkklaar, Sejarah Gereja, 114-118, 126-127. van Den End, Harta dalam Bejana, 142. 39 di berbagai sisi kehidupan, dan mengembalikannya menurut pandangan yang terdapat pada kehidupan Gereja Perdana. Kedudukan Gereja dan negara ditempatkan sejajar (iucta positie) sebagai mitra untuk mewujudkan keselamatan atau membangun kesejahteraan segenap masyarakat. Ajaran extra ecclesiam nulla salus dengan berbagai tata peribadahan yang berhubungan dengannya diperiksa dan dikembalikan pada asas-asas yang terdapat pada pandangan Gereja Perdana.75 Salah satu upaya reformasi yang mendasar untuk memulih-kan kedudukan Gereja maupun umat pada abad pertengahan menurut tata kebiasaan Gereja Perdana adalah mengembalikan hak dan tanggung jawab yang melibatkan peran serta umat secara penuh di dalam sakramen maupun pelayanan firman (pengajaran) dengan menggunakan bahasa setempat yang biasa digunakan umat.76 Salah satu hasil reformasi Gereja di dalam kehidupan peribadahan umat di atas adalah Liturgi Protestan. Dibandingkan dengan Liturgi Roma, Liturgi Protestan pada masa-masa awal perkembangannya memperlihatkan adanya keragaman yang cepat. Salah satunya adalah Liturgi Calvin, yang hingga perkembangannya di masa kini dipakai juga oleh Gereja Kristen Jawa. Ada perbedaan yang menjadi kekhasan pandangan reformasi Gereja di dalam Liturgi Calvin. Pertama, susunan di dalam Liturgi Calvin dipandang lebih sederhana dibandingkan dengan Liturgi Roma yang dipenuhi dengan berbagai macam ritual. Sewaktu ibadah di mulai, disampaikan salam dan berkat yang didalamnya terkandung makna seruan (votum) 75 76 van Den End, Harta dalam Bejana, 166-176, 188-191. Berkhof, Enklaar, Sejarah Gereja, 98, 131, 135. 40 maupun pengakuan pertolongan Tuhan di dalam pelaksanaan ibadah (adiutorium) yang disambut dengan pujian umat dan dilanjutkan dengan pengakuan dosa (konfesi). Setelah itu disampaikan berita anugerah (absolusi) dan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah bagi kehidupan iman umat yang baru (komandemen) yang disambutan dengan kesanggupan oleh umat (aklamasi). Selanjutnya umat menghaturkan persembahan syukur yang terkumpul (kolekta) dan disambung dengan pemberitaan firman melalui pembacaan Alkitab secara berangkai serta berkesinambungan (leksio kontinua) maupun penyampaian pengajaran (homili). Pemberitaan firman itu diteruskan dengan doa permohonan umat (intersesi) maupun doa sakramen perjamuan, dan pelayanan sakramen (perjamuan ataupun baptis) menurut rumusan serta aturan yang berlaku. Namun bagi yang tidak melaksanakan sakramen tiap Minggu, maka peribadahan dapat langsung ditutup dengan pengucapan rumusan pengakuan iman (kredo) dan penyampaian berkat (benediksi) sewaktu hendak pembubaran dalam perutusan (dismissi). Kesederhanaan tersebut diyakini memiliki dasar pada Kitab Suci maupun kebiasaan Gereja Kuno.77 Kedua, Liturgi Calvin tidak mengistimewakan ritual sebagaimana terdapat di dalam Liturgi Roma, melainkan pemberitaan firman yang diuraikan dalam ajaran berdasarkan rangkaian pembacaan kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dan Injil secara berkesinambungan bersama dengan perutusan yang diteguhkan dalam berkat. Ketiga, roti dan anggur Perjamuan Kudus yang 77 Thompson, Liturgies of the Western Church, 185-224. 41 diletakkan di atas meja perjamuan dipandang bukan penjelmaan kurban Yesus Kristus di atas altar untuk penebusan yang bisa diulang-ulang sebagaimana pengertian yang ada pada Liturgi Roma, melainkan sebagai tanda dan pengingat bagi setiap orang percaya yang ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan akan karya korban penebusan dosa beserta janji kehidupan kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, yang keempat bahwa kelayakan yang memberikan pengudusan umat dihadirat Allah bukan karena anggur dan roti yang disucikan melalui ritual seperti yang ada pada Liturgi Roma, melainkan karena kasih karunia yang bekerja melalui pengujian batin diri setiap pribadi umat yang hendak mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan sebagai disiplin kehidupan iman. Adapun yang terakhir, kelima adalah doa-doa umat untuk kesejahteraan atau keselamatan tidak untuk para suci ataupun melalui mereka kepada Tuhan seperti yang terdapat di dalam Liturgi Roma, tetapi merupakan permohonan langsung kepada Tuhan agar memberikan berkat dan pertolongan kepada negara dan para memimpinnya supaya dapat menjalankan tanggung jawab menurut tugas-tugas mereka, serta kepada gereja dan umat agar bisa menjalankan kehidupan yang baik menurut ajaran iman yang benar oleh ketaatan.78 Segala sesuatu yang ada di dalam periode perkembangan Gereja pada masa Reformasi Gereja di atas, apabila dicermati melalui perbandingan yang terdapat pada periode sebelumnya, ada pola maju pada jamannya yang 78 Thompson, Liturgies of the Western Church, 185-224. 42 digunakan sebagai pendekatan untuk mewujudkan pemahaman keselamatan di dalam kehidupan umat, yaitu pola pendidikan atau pengajaran. Cara yang dimiliki umat pada masa ini dipandang memiliki hubungan dengan budaya yang sedang menonjol saat itu, yaitu Renaisance yang berpegang pada pemikiran akan kesadaran diri manusia sebagai tindakan kritis dan ilmiah, serta Barok yang menekankan kebebasan manusia untuk mengungkapkan kemampuan diri sebagai hak asasinya.79 Periode terakhir di dalam perkembangan Gereja hingga saat ini adalah masa Pasca Reformasi Gereja. Sebutan ini memang belum baku. Apabila menggunakan istilah Rasid, maka istilah untuk menyebut masa tersebut adalah jaman modern. Sebutan itu berpijak pada perkembangan Gereja pada abad ke-20 dengan keterbukaan yang luas terhadap berbagai sisi yang menjadi kehidupan umat di dunia ini.80 Namun terkait dengan perhatian yang kian terbuka pada jaman tersebut, Martasudjita memberikan sebutan lain, yaitu jaman pembaruan hingga abad ke-20. Dasarnya adalah gerakan yang telah dimulai semenjak reformasi Gereja melalui Konsili Trente dan berpuncak pada Konsili Vatikan II, di mana Gereja semakin membuka diri terhadap umat dalam keikutsertaan mereka di tengah peribadahan selaras dengan sisi-sisi dan pergumulan nyata dari umat saat ini.81 Apapun sebutannya, masa-masa tersebut adalah masa yang memiliki hubungan erat dan memang merupakan kelanjutan dari masa reformasi Gereja. Karena itu di 79 van Olst, Alkitab dan Liturgi, 92-93. Rasid, Pembimbing ke dalam Sejarah Liturgi, 192-193. 81 Martasudjita, Liturgi, 77-96. 80 43 dalam periode ini bisa disebut juga sebagai masa Pasca Reformasi Gereja, atau Jaman Gereja Masa Kini. Pemahaman akan perubahan di dalam perkembangan pada masa ini tidak bisa hanya dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh kalangan Gereja Protestan saja, tetapi juga pada kehidupan Gereja Katholik (Gereja Romawi Barat). Sebab di antara keduanya sama-sama melakukan pembaruan. Di antara Gereja Protestan maupun Gereja Katholik pada masa ini sama-sama berusaha untuk semakin dapat memberikan hak dan tanggung jawab umat sebagai pengakuan dan pemberian tempat atas peran serta mereka di dalam tata peribadahan dengan mengacu pada tradisi Gereja Perdana. Bahkan kesadaran oikumenis beserta dengan pergumulan masyarakat dan budaya di mana umat tinggal dan hidup di dalamnya juga semakin mendapat tempat yang penting sebagaimana dikenal adanya gerakan-gerakan oleh lembaga-lembaga internasional bersama dengan Dewan Gereja Dunia ataupun kebijakan Vatikan dengan istilah adaptasi, kontekstualisasi, inkarnasi, inkulturisasi, enkulturisasi, akulturisasi, indigenesasi (pempribumian), dan lain sebagainya, untuk mendaratkan teologi bagi liturgi peribadahan umat Kristen itu sendiri. Pada akhirnya meskipun secara praktis ada persamaan, namun pada asas keyakinan dan pemahaman yang terungkap lewat pola yang digunakan untuk mewujudkan keselamatan umat di antara kedua Gereja itu tetap tidak bisa disamakan. Gereja Katholik masih tetap bertahan dengan pola ritualnya, sedangkan Gereja Protestan begitu kuat dengan pendekatan pengajaran44 nya. Pola masing-masing Gereja tersebut sangat nyata dipengaruhi oleh budaya dan sejarah perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. 2.2.5. Liturgi dan Budaya Merunut uraian sejarah singkat asal-usul dan bagaimana liturgi Kristen berkembang dari penjelasan di atas, ada salah satu segi penting yang begitu berperan di dalam nya, yaitu budaya. Sebagai bagian dari kebudayaan, tata peribadahan yang merupakan bentuk dari ritual keagamaan itu tidak lepas dari pengaruh budayanya.82 Seperti dinyatakan oleh Soerjono Soekamto, bahwa ritual adalah suatu sisi keagamaan yang menjadi salah satu unsur pokok pembentuk kebudayaan sekelompok orang atau masyarakat sebagai jalinan erat dan utuh di dalam keberadaan mereka.83 Karena itu pada diri liturgi bisa pula melekat unsur-unsur lain dari sebuah kebudayaan, seperti pandangan hidup, bahasa, seni, peralatan, pencaharian masyarakat, maupun penataan hidup bersama yang dimilikinya. Selain dari kajian asal usul Paskah dan Baptisan di atas, hubungan liturgi Kristen dengan budaya dapat dilihat pada tafsir yang menjadi sudut teologis. Dari sudut teologis Kristen, kematian Yesus Kristus di kayu salib diyakini sebagai korban penebusan dosa yang sejajar dengan gagasan tentang domba korban penebusan dan pengudusan umat seperti yang 82 83 Paul Tillic, Theology of Culture (New York: Oxford University Press, 1959), 47. Soerjono Soekamto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 191-194. 45 terdapat di dalam akar keagamaan orang-orang Yahudi,84 seperti dicatat pula dalam beberapa tulisan-tulisan ayat Kitab Suci Perjanjian Baru.85 Keterkaitan itu semakin jelas dengan pengabsahan gagasan dasar pandangan Kristen melalui penggunaan pustaka-pustaka yang berasal dan yang digunakan pula oleh Agama Yahudi. Adapun roti dan anggur sebagai sarana dalam sakramen yang menjadi lambang gagasan dasar dan pusat peribadahan umat Kristen sendiri juga menunjukkan wujud kebudayaan Yahudi. Makanan roti dan minuman anggur adalah pangan olahan orang-orang Yahudi yang banyak dihidangkan untuk makan pokok keluarga maupun pesta. Keduanya sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi kehidupan orang Yahudi sejak jaman kuno, termasuk sebagai barang persembahan di dalam upacara keagamaan.86 Beberapa ayat di dalam teks-teks Kitab Suci Perjanjian Lama juga menyebutkan bahwa roti adalah barang persembahan bakaran yang sama seperti hewan-hewan korban bakaran. Sedangkan anggur merupakan barang persembahan curahan sama seperti darah hewan korban bakaran yang sebelumnya disembelih terlebih dulu dan darahnya dituangkan di atas korban yang sedang dibakar itu.87 84 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 69-71. 85 Yohanes 1:29, 36, I Korintus 5:7b, Ibrani 9:13-14, I Petrus 1:18-19 LAI. Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 74-78, 521-526. 87 Keluaran 22:29, 29:40, Imammat 23:13, Bilangan 15:5, 7, 18:27, 28:14, Ulangan 12:17, I Samuel 1:24, Ezra 6:9, Nehemia 10:36-37, 13:5, 12 LAI. 86 46 Demikian pula dengan berbagai kelengkapan dan lambang-lambang yang berkembang di dalam peribadahan hingga sekarang. Pada Kekristenan awal belum banyak ditemukan lambang yang digunakan di dalam peribadahan ataupun liturginya. Beberapa lambang yang ada pada waktu itu masih berupa anggur, roti, dan air. Namun dengan berubahnya suasana keadaan waktu dan persebaran umat Kristen muncullah lambang-lambang lain, yang salah satu kegunaannya lebih mengarah pada makna tanda pengenal bagi satuan mereka di tengah lingkungan maupun kedudukan Kekristenan di dalam masyarakat atau negara, serta penunjuk rangkaian masa tahunan di dalam almanak tahunan peribadahan. Sewaktu terjadi tekanan dan tersingkir dari pusat masyarakat Yahudi maupun kemudian juga di pusat masyarakat Romawi, maka di tengah Kekristenan lahirlah lambang pengenal untuk melakukan hubungan di dalam kesatuan umat berbentuk gambar salib jangkar dan ikan.88 Dilihat dari sudut kebudayaan, keberadaan lambang-lambang itu dimungkinkan berasal dari budaya masyarakat para mengikut Yesus mula-mula, yaitu masyarakat pisisir Galilea yang daerahnya dikuasai bangsa Roma, dengan kehidupan sebagai nelayan.89 Akan tetapi, pada waktu itu semua lambang di atas belum memiliki hubungan secara langsung di dalam peribadahan Kristen. Baru setelah jaman yang memberikan keterbukaan makin luas dari penguasa Roma, maka lambang-lambang tadi mulai masuk di dalam peribadahan dan secara berangsur dijadikan sebagai sarana liturgi. Tidak hanya 88 89 van Den End, Harta dalam Bejana, 29. Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 74-78, 521-526. 47 roti, anggur, dan air saja yang digunakan sebagai lambang di dalam peribadahan, tetapi mulai terdapat berbagai lambang lain, seperti meja altar, salib dan relik, pakaian para imam, dupa, gambar-gambar lambang dan warna-warna masa tahunan almanak Gerejawi, bentuk bangunan dan tata ruang beserta perabotnya, musik maupun nyanyian ibadah, bahkan tata gerak tubuh dan tata peran umat di dalam peribadahan. Kemunculan lambang-lambang itu tidak lepas dari budaya yang ada di lingkup kehidupan umat, khususnya kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani. Yang tidak kalah penting dalam perkembangan liturgi yang bersinggungan dengan budaya secara lebih lanjut adalah gagasan keselamatan yang tidak lagi cukup dalam pribadi Yesus Kristus seperti kepercayaan baku Kekristenan awal, namun pada akhirnya juga ada pribadi lain yang dipandang oleh kaum tertentu ikut menentukan, yaitu santo ataupun santa. Semua perkembangan yang ada di dalam liturgi peribadahan Kristen tersebut disebabkan adanya pengaruh dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat di mana umat Kristen hidup bertumbuh, yaitu faham Yahudi Yunani (Hellenistic Judaism) yang khas dengan sisi pengetahuan filsafat dalam diri kaum Yahudi Diaspora di negeri-negeri daerah Mediteranian, dan dunia kepercayaan Pagan Yunani Roma (Pagan Roman Hellenistic World) yang terwujud dalam teologi, pandangan keselamatan dan pemahaman diri Gereja, maupun tata hubungan yang tersusun di dalam kelembagaan umat.90 90 Brox, A History of the Early Church, 11-15. 48 Kelekatan liturgi sebagai salah satu wujud tindakan keagamaan dengan budaya tersebut ditegaskan pula oleh Retnowati. Meskipun agama merupakan bagian dari kebudayaan, secara sosiologis di antara keduanya saling berhubungan erat sehingga sulit dipisahkan dan dibedakan perannya di dalam kehidupan manusia.91 Pada sisi lain, hubungan liturgi sebagai salah satu sisi agama dengan kebudayaan itu secara khusus juga nampak dalam kajian Emile Durkheim yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan kegunaannya. Dari kajian Durkheim ada beberapa kegunaan yang menjadi hubungan ritual keagamaan dengan kehidupan umat atau masyarakat. Pertama, ritus yang diungkapkan dengan larangan-larangan (tindakan negatif) maupun pengorbanan dan persembahan (tindakan positif) pada dasarnya menyatakan pandangan-pandangan yang menjadi kesadaran kehidupan bersama (ideologi) dari sekelompok masyarakat sebagai kenyataan dan pusat keyakinan yang disebut dengan istilah “illahi” atau yang “sakral”.92 Sehubungan dengan peribadahan Kristen, maka liturgi dapat dipandang memiliki kegunaan yang sama. Segala sesuatu yang ditunjukkan maupun yang dipergunakan di dalam liturgi dengan segala bentuk lambang-lambang ataupun tanda-tanda yang dipertunjukkan akan selalu mengandung arti atau mengungkapkan makna ideologi yang ditinggikan dan diimani oleh umat atau Gereja. 91 Retnowati, Agama dan Kebudayaan (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2009), 4-5. 92 Emile Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 471-585, 497. 49 Kedua, ritus yang dilakukan oleh umat akan bekerja di dalam pikiran setiap pribadi sekelompok masyarakat dan memberikan ingatan-ingatan terhadap pandangan-pandangan dasar sebagai muatan moral kehidupan melalui peristiwa-peristiwa yang diwujudkan dalam festival dan perayaan maupun kebiasaan-kebiasaan bersama yang dihadirkan kembali sebagai upacara-upacara keagamaan.93 Hal sama ada juga di dalam peribadahan Kristen. Pandangan-pandangan dasar kehidupan iman yang terkandung di dalam segala sesuatu yang ditunjukkan maupun digunakan pada liturgi peribadahan umat akan menjadi wahana transformasi nilai-nilai penting bagi kehidupan moral mereka. Ketiga, ritus yang dilaksanakan secara terus-menerus dapat menumbuhkan dan memperkuat ikatan antar anggota solidaritas sekelompok masyarakat oleh karena nilai-nilai dasar kehidupan yang menjadi moralitas bersama; demikian pula sebaliknya. Setiap orang yang terus-menrus ada di dalam upacara-upacara keagamaan akan merasa disatukan sekaligus disadarkan akan kesatuan yang menjadi kenyataan yang ada di dalam kehidupan mereka itu.94 Demikian pula dengan pelaksanaan liturgi. Setiap orang yang senantiasa terlibat di dalamnya akan merasakan ikatan di tengah kebersamaan umat; atau lebih pasnya adalah bahwa liturgi akan menimbulkan suatu ikatan perasaan dan kesadaran yang sama di antara para anggota umat sendiri. 93 94 Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life, 538-539. Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life, 501, 554. 50 Keempat, di sisi lain ritus juga menjadi wahana peneguhan dan pembaruan keberadaan sekelompok masyarakat itu sendiri akan kesatuan sekaligus hakikat dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan, melalui keikutsertaan secara terus-menerus.95 Kenyataan itu juga nampak di dalam peribadahan Kristen. Ketika umat selalu mengikuti pelaksanaan liturgi, maka keberadaan mereka akan terjaga dan senantiasa akan bertahan. Akhirnya, yang kelima bahwa ritus yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat bukan saja berkaitan dengan pemeliharaan akan sejarah keyakinan di masa lalu ataupun juga dengan tujuan-tujuan beserta dampak tindakan lahiriah yang hendak dicapai, tetapi sesungguhnya berkaitan dengan masalah pelestarian jatidiri moral sekelompok masyarakat itu juga.96 Pikiran ini tidak berbeda dengan liturgi peribadahan Kristen yang sesungguhnya juga menjadi alat untuk mendapatkan dan sekaligus membangun identitas berdasarkan keyakinan yang menghasilkan nilai-nilai moral bagi kehidupan bersama dari umat. Beberapa pokok pandangan kegunaan liturgi dari Durkheim tersebut pada intinya ada keselarasan dengan faham Calvin. Dalam pandangan Calvin, liturgi peribadahan Kristen memiliki keterkaitan dengan makna inti dari sebuah keyakinan maupun nilai-nilainya, yang diungkapkan melalui seperangkat tata perilaku tertentu beserta dengan tindakan pengeja- 95 96 Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life, 538-539. Durkheim, The Elementary Form of The Religious Life, 533. 51 wantahannya.97 Pandangan tentang inti iman itu adalah pengalaman umat akan tindakan penyelamatan Allah yang dinyatakan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus yang disebut Krsitus.98 Sedangkan seperangkat tata perilaku dan tindakan pengejawantahannya tersebut adalah kepercayaan Kristen mendasar yang menjadi sumber nilai-nilai pedoman bagi kehidupan umat (etika), yang diungkapkan dengan merumuskannya dalam seperangkat ajaran (dogma), tata aturan (hukum), tata perhimpunan (organisasi), maupun tata peribadahan (ritus).99 Singkatnya, liturgi adalah salah satu sisi ungkapan keagamaan yang dinyatakan melalui kebudayaan umat sebagai kesatuan keberadaan hidup mereka. Karena itu pada hakikatnya di dalam liturgi terdapat suasana dan keadaan tertentu dan khas atau kontekstual dari kehidupan umat di tengah masyarakat. Sebab gagasan-gagasan, lambang-lambang dalam wujud benda, gambar, warna, maupun tata perilaku, aneka piranti sesaji maupun perabot, bahkan musik dan bentuk bangunan atau tempat yang dipergunakan dan terangkai untuk menyatakan pandangan dasar yang ditinggikan umat dalam sebuah liturgi merupakan hasil kebudayaan yang berkembang dalam suasana dan keadaan kehidupan masyarakatnya. 97 Christiaan de Jonge, Apa Itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 165-166. 98 Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 582-583. Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 147. 99 52 2.2.6. Kontekstualisasi Litugi dalam Budaya Serangkaian kenyataan yang terdapat pada beberapa pembahasan di atas menjelaskan pula adanya kontekstualisasi liturgi dalam Kekristenan di tengah budaya di mana umatnya hidup berkomunikasi dan menjalin hubungan di dalamnya. Dengan kata lain, sesungguhnya terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh Kekristenan terhadap unsur-unsur budaya di dalam ibadah umat. Sebagaimana diungkapkan pada bagian dasar liturgi, tindakan itu dibarengi dengan penafsiran-penafsiran untuk memberikan pemaknaan yang dipandang selaras dengan gagasan di dalam liturgi itu sendiri. Ada unsur-unsur penting terkait dengan penafsiran dan pemaknaan di dalam kontekstualisasi. Unsur pertama, kontekstualisasi adalah bukan sekedar masalah praktis, melainkan praksis sebagai masalah utama, yaitu bagaimana orang Kristen memahami dirinya di dalam suasana keberadaan yang nyata dan berwujud. Unsur kedua, kontekstualisasi bukan sekedar pergantian wujud luar kebudayaan, tetapi isinya sehingga kemasannya mesti terus dipertahankan atau dapat diubah sesuai dengan wujud yang ada di dalam kebudayaannya itu. Unsur ketiga, kontekstualisasi terkait dengan persoalan apakah iman dapat dihayati melalui dan di dalam budaya umat itu sendiri. Akhirnya, unsur yang keempat, kontekstualisasi juga meliputi kategori-kategori teologis etis yang bukan sekedar cara penerapan suatu nilai ataupun pola ke dalam suasana keberadaan setempat, melainkan apakah nilai ataupun pola tersebut memiliki titik pertemuan dengan pandangan hidup atau pandangan dunia setempat, sehingga dalam 53 menyusun teologi yang saling berkaitan penting bagi konteks setempat tidak mengabaikan tempatnya di tengah universalitas Injil dengan menghindarkan perasaan inferior terhadap teologi-teologi yang sudah tersusun.100 Unsurunsur kontekstualisasi tersebut memiliki persinggungan dengan definisi teologi kontekstual yang dinyatakan oleh Huang Po Ho, yaitu suatu teologi yang mengambil konteks, situasi dan kondisi daerah tempat tinggal, sejarah dan kebudayaan umat di tengah masyarakat sebagai sumber refleksi dan pengakuan iman, serta untuk membangunan teologi yang dapat membentuk identitas relevan dengan konteksnya. Selanjutnya, untuk membuat kontekstualisasi sebuah teologi kontekstual secara umum ada empat langkah, yaitu transplantasi, translasi, partisipasi, dan rekonstruksi. Langkah transplantasi atau pencangkokan, yaitu upaya memasukkan semua teologi serta pengajaran teologi tradisional atau Teologi Barat, yang banyak dikuasai oleh para misionaris dalam Gereja ke suatu tempat, bahkan teologi yang dibentuk oleh negeri mereka. Kekhasan langkah itu adalah permusuhan dengan budaya pribumi yang dicap sebagai “berhala”, perlu dihancurkan dan diganti. Langkah translasi atau penterjemahan ialah tindakan Gereja di suatu tempat tertentu mengetemukan kebudayaan setempat sebagai alat penafsiran tepat guna. Penterjemahan Alkitab bagi bahasa-bahasa setempat, komunikasi pokokpokok pengertian teologis, dan ungkapan-ungkapan liturgi beserta seluruh 100 Emanuel Gerrit Singgih, Dari Israel ke Asia: Masalah Hubungan Antara Kontekstualisasi Teologi dengan Interpretasi Alkitabiah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 8-28, 118-119. 54 unsur kebudayaan setempat diperlukan sebagai sarana. Sikap Gereja terhadap kebudayaan setempat bergeser dari menentang kepada pemanfaatan sebagai alat penterjemahan, pengungkapan, pemakluman. Meskipun sikap Kekristenan berubah dan kebudayaan setempat dinilai dengan cara lebih positif, masih saja menerimanya sebagai peran atau piranti untuk menghubungkan keberadaan pokok-pokok pengertian maupun isinya, yaitu: kedudukan teologis, pemikiran-pemikiran, serta isi yang tetap tradisional. Langkah partisipasi atau peran serta yaitu tahap membangun teologi yang menekankan cara lebih berdaya, dengan melihatnya bukan saja sebagai perangkat pemikiran ataupun refleksi iman, tetapi merupakan tekat kuat untuk ikut serta di dalam karya rencana penyelamatan Allah. Pada langkah ini upaya teologi tidak selamanya menerima kesederhanaan kebudayaan setempat sungguh-sungguh sebagai alat untuk mengungkapkan, tetapi harus mengambil sejarah dan kebudayaan setempat sebagai sasaran dan tujuan teologi agar mendorong Gereja-Gereja maupun orang-orang Kristen ikut serta dalam missi dan bersaksi, merubah dan membuat perubahan sejarah maupun kebudayaan masyarakat sehingga Gereja dapat hidup bersama dan menciptakan kemungkinan bagi umat mengalami karya penyelamatan Allah. Langkah rekonstruksi atau membangun ulang yaitu berteologi yang tidak hanya mengambil sejarah dan kebudayaan setempat sebagai sasaran ataupun tujuan teologi, tetapi juga menjadikan diri teologi itu sendiri sebagai sasaran serta tujuan pembaruan dan membuat perubahan. Pada tahap itu Gereja sedang mendapatkan kembali jatidirinya sebagai 55 Gereja umat setempat, bergumul dengan cara berteologi yang didasarkan pada sumber-sumber yang dikenal dari konteks kehidupan, sejarah, dan kebudayaan mereka.101 Langkah-langkah kontekstualisasi tersebut di dalam proses perkembangan membangun teologi kontekstual, perwujudannya dapat dilihat dalam dua bentuk cara pendekatan, yaitu pendekatan indigenisasi dan pendekatan kontekstualisasi. Pendekatan indigenisasi atau pembribumian yang disamakan dengan tahap pendekatan translasi adalah pendekatan yang membawa masuk unsur-unsur kebudayaan setempat untuk menterjemahkan dan memoles teologi yang mereka terima dari Gereja-Gereja Barat, sehingga tidak mengubah isi dan inti teologi yang diterima pula dari para missionaris Barat. Semua teologi itu dihiasi dengan unsur-unsur budaya setempat untuk pengungkapan dan mengkomunikasikannya secara lebih baik dengan masyarakat setempat. Pokok-pokok pengertian maupun pemikiran- pemikiran yang sama dikenali, supaya mencapai tujuan gagasan-gagasan teologi asal yang luas dengan cara ramah dan menarik hati melalui unsurunsur kebudayaan lazim di masyarakat. Adapun pendekatan kontekstualisasi yang dipandang sebagai cara pewujudan “inkarnasi” Yesus Kristus adalah pendekatan yang mengharuskan teologi berperan serta dalam konteks, dan melekat erat dengan lingkungan masyarakat di tempat Gereja hadir. Pendekatan ini perlu terus dipertajam sesuai dengan perubahan konteks dan lingkungannya. Karena teologi yang mengakar pada lingkungan sejarah dan 101 Huang Po Ho, No Longer a Stranger, 31-33. 56 masyarakat, harus dikerjakan dengan tekat semangat ikut serta tak henti di dalam missi Kekristenan di tengah konteks berwujud.102 Pandangan mengenai cara yang ada di dalam perkembangan liturgi tersebut juga digagas secara mendalam oleh Anscar J. Chupungco. Menurutnya, kontekstualisasi atau penyesuaian yang disertai dengan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan merupakan ciri khas abadi liturgi Kristen sejak awal keberadaannya hingga sekarang. Dimulai dari tindakan Yesus yang meninjau dan memberi arah pemikiran baru terhadap ajaran maupun adat Yahudi serta mengilhaminya dengan misteri ke-Messias-anNya melalui lambang perjamuan Paskah, maka dari waktu ke waktu penyesuaian liturgi beserta pemaknaan terhadap berbagai bentuk kebudayaan dilakukan juga oleh para penerus atau Gereja hingga sekarang selaras dengan lingkungan kehidupannya.103 Penafsiran yang dimaksud adalah pendekatan terhadap sejarah liturgi yang senantiasa mengalami perubahan pelahan-lahan agar umat di dalam kehidupan peribadahannya dapat menemukan sejumlah hubungan maupun kesinambungan perkembangan bentuk-bentuk liturgi. Selain manfaat itu, pendekatan penyesuaian berguna juga untuk melihat bentuk-bentuk liturgi asli supaya mendapatkan kemurnian tafsiran terhadap pelaksanaanpelaksanaan liturgi yang masih ada hingga sekarang.104 Karena itu kontekstualisasi pada liturgi dipandang sebagai perlakuan sekaligus pendekatan 102 Huang Po Ho, No Longer a Stranger, 54-57. Anscar J. Chupungco, Penyesuaian Liturgi dalam Budaya (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 13-56. 104 Chupungco, Penyesuaian Liturgi dalam Budaya, 13-15. 103 57 terhadap kesamaan-kesamaan akan nilai-nilai budaya beserta dengan bentuk-bentuk kebiasaan di dalam pelaksanaan liturgi untuk menanamkan gagasan dasar yang dimilikinya. Sebagai suatu metode, pandangan mengenai kontekstualisasi liturgi tersebut terjabar ke dalam empat pokok model, yaitu model kompromi, model adaptasi, model asimilasi, model substitusi. Maksud kompromi atau pemufakatan adalah upaya kesefahaman karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu keyakinan yang sulit menyatu demi terwujudnya keutuhan nilai gagasan utama iman di tengah peribadahan umat. Adapun adaptasi atau penyelarasan merupakan upaya menanamkan secara berangsur-angsur ibadah Kristen ke dalam sejarah keselamatan yang teranyam pada kehidupan manusia di dunia atau budayanya, sehingga peristiwa yang disaksikan Kitab Suci kembali disadari melalui liturgi, di mana misteri Kristus hadir di dalamnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan asimilasi atau pemaduan adalah upaya pendekatan terhadap budaya dengan menghormati apa yang luhur dan bermanfaat dalam masyarakat untuk dijadikan sarana yang dapat dipergunakan secara baik di dalam liturgi melalui pemberian makna baru secara Kristiani. Sedangkan maksud substitusi atau penggantian adalah upaya pendekatan dengan melakukan penggantian unsur-unsur budaya yang bertentangan sama sekali dengan 58 pandangan iman Kristen sedemikian rupa sehingga unsur-unsur itu lenyap sama sekali melalui gagasan-gagasan yang dipandang sama.105 Kontekstualisasi liturgi terhadap budaya beserta dengan pembedaan dalam beberapa model di atas tidak bisa dipisahkan dari tiga asas pokok. Asas pertama adalah hakikat Gereja sebagai kelanjutan dari penjelmaan Sabda Allah.106 Kecuali dosa, Sang Sabda telah merasuki keadaan manusia dan mengikat diri dengan sejarah, kebudayaan, tradisi, maupun agama bangsaNya. Penjelmaan Sang Sabda di dalam daging adalah keberadaanNya sebagai seorang Yahudi. Sang Sabda menjadi manusia bukan sekedar manusia tanpa identitas, tetapi manusia tertentu dengan ciri-ciri khas bangsa di tempatNya hadir. Dia mewarisi kecenderungan kodrati, ciri-ciri khas, bakal spiritualitas dan cara mengungkapkan diri yang khas Yahudi. Sejarah penjelmaan menuntut Dia menyamakan diri dengan bangsaNya dalam hati dan budi, dalam daging dan darah. Asas ini membuka pengertian bahwa dengan tidak membatasi lingkup penjelmaan Sang Sabda sebagai manusia, pandangan semacam itu menjamin universalitas Kristus dan InjilNya. Dengan kenyataan bahwa Sang Sabda menjelma menjadi seorang Yahudi, memberikan jaminan dalam kebangkitanNya yang dapat menjelma dalam setiap bangsa dan kebudayaan melalui iman Gereja dan perayaan misteriNya. Dengan demikian perluasan penjelmaan Gereja di berbagai suku bangsa dan kebudayaan akan merupakan perluasan dari universalitas Kristus. Karena itu, penyesuaian bukan masalah mana suka, melainkan 105 106 Chupungco, Penyesuaian Liturgi dalam Budaya, 15-51. Chupungco, Penyesuaian Liturgi dalam Budaya, 75-80. 59 keharusan teologis yang timbul dari tuntutan misteri inkarnasi. Gereja tidak dapat tetap menjadi “orang asing” di tengah suatu bangsa dengan siapa dia hidup, tetapi harus menjadi anak bangsa itu. Dengan memandang bahwa pewahyuan Kristen tetap memiliki keunggulan atas segala ciptaan manusia, maka perwujudannya harus ditemukan pada unsur pribumi yang dapat memperjelas amanat liturgi. Namun, jika menemui keadaan pelik, Gereja harus memiliki alasan teologis yang kuat untuk bisa mengakomodasi tuntutan iman di dalam liturgi sehingga liturgi tidak menjadi asing bagi setiap kebudayaan secara khas melalui susunan, bahasa, ataupun lambanglambang, tanpa harus kehilangan isi dasarnya. Asas yang kedua, adalah liturgi sebagai penghormatan atas keagungan Illahi, yang pada hakikatnya di dalam liturgi terdapat wujud pertemuan pribadi dengan Allah sebagai hal yang utama.107 Sebabnya adalah di dalam liturgi sesungguhnya terdapat makna pendidikan (kateketis), di mana Allah berbicara kepada umatNya, dan di situ pulalah Kristus senantiasa mewartakan InjilNya dalam misteri Paskah yang menjadikan liturgi sebagai pewartaan iman resmi dari Gereja. Singkatnya, pusat peribadahan Kristen adalah Sabda Allah, yang di dalamnya Kristus menjadi inti liturgi yang tidak bisa digantikan oleh pikiran atau ideologi manusia. Namun demikian kedalaman penyesuaian liturgi tetap dapat diukur dengan penggunaan bahasa yang mencerminkan pikiran umat, sehingga penggunaan lambanglambang dan corak pribumi dapat membantu menciptakan suasana pribumi 107 Chupungco, Penyesuaian Liturgi dalam Budaya, 81-93. 60 dan menjelaskan maksud-maksud tanda liturgis. Selama Gereja menggunakan bahasa asing yang pola pikir dan ekspresinya asing pula bagi umat, semua usaha untuk mengadakan penyesuaian tetapi terasa dibuat-buat. Asas ketiga adalah tuntutan kultural untuk membuat liturgi siap dipakai dan memiliki hubungan yang penting bagi setiap kebudayaan yang di dalam-nya mengandung keseluruhan nilai manusiawi, keseluruhan tradisi beserta upacara kemasyarakatan maupun keagamaan, keseluruhan pola pengungkapan yang semuanya berakar di dalam sifat-sifat khas suatu bangsa melalui cara berpikir, berbahasa, berkesenian, maupun kreasi batin secara spontan terhadap kenyataan kehidupan yang tengah terjadi, serta perilaku yang mengungkapkan kepekaan intelektual, emosional, dan tindakan atau aksi. Namun, penyesuaian liturgi tidak berarti kembali ke cara-cara hidup primitif atau yang telah ditinggalkan, maupun dalam arti melakukan pendekatan futuristik atau mengambil bentuk-bentuk budaya yang sedang dalam proses asimilasi. Kontekstualisasi selalu terkait dengan nilai dan tradisi yang telah baku, yang telah membentuk kehidupan agama, keluarga, kemasyarakatan serta nasional bangsa dalam waktu cukup lama hingga mapan. Karena itu yang harus dicari di dalam peribadahan adalah unsur kebudayaan yang sudah mantap, yang sungguh-sungguh diakui oleh bangsa itu sebagai miliknya sendiri, dan dapat diresapi melalui bahasa ataupun upacara mereka. 61 2.3. Budaya Jawa Telah dinyatakan di dalam batasan istilah pada Bab I, bahwa yang dimaksud dengan budaya Jawa adalah seperangkat pikiran dan tindakan atau perilaku dari masyarakat yang memiliki faham Jawa, beserta dengan segala wujud maupun hasilnya. Faham Jawa disebut juga Kêjawén, yaitu pandangan kehidupan yang didasarkan pada pokok pengertian keselarasan (harmoni) antara kenyataan jagad gêdhe (makro kosmos) dengan jagad cilìk (mikro kosmos) sebagai asas keberadaan dan keselamatan hidup orang Jawa.108 Jagad gêdhe adalah seluruh kenyataan yang ada di alam semesta, dan jagad cilìk adalah kenyataan diri pribadi seseorang sebagai manusia yang keberadaan hidupnya merupakan bagian tidak terpisahkan dan berkaitan erat dengan kenyataan yang ada di alam semesta itu. Kedua jagad itu pada dasarnya satu kesatuan sebagai keteraturan. Penyimpangan salah satu dari jagad itu akan berpengaruh pada keberadaan jagad yang lainnya, dan entah besar atau kecil pasti akan menimbulkan kekacauan atau kaos yang mengakibatkan mala-petaka, derita, dan akhirnya sirna. Karena itu jagad gêdhe dan jagad cilìk harus selalu selaras, dijaga hubungannya secara harmonis agar terpelihara dan senantiasa tercipta kehidupan, dengan istilah māmayu hayunìng bawânâ (ikut memelihara keindahan dunia semesta). Apapun wujud dan keadaan di tengah dunia ini telah ditetapkan (pinêsthi) dan semuanya sudah ditata oleh Tuhan (Hyang). Masing-masing memiliki kedudukan serta daya guna yang saling berhubungan dan tidak bisa 108 Yana, Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa, 18-21. 62 ditiadakan. Seperti diungkapkan oleh Niels Mulder bahwa dalam kepercayaan orang Jawa, kehidupan di dunia sesungguhnya merupakan bagian dari kesatuan keberadaan segala sesuatu dengan berbagai peristiwa yang telah terjadi bukan sebagai kebetulan, tetapi sudah dirancang dan ditentukan oleh Hyang Maha Esa, Sang Pencipta kehidupan (Hyang Suksma) dan Asal-Usul (sumber awal kejadian dan tempat kembalinya) semua ciptaan dalam hubungan tertata dan saling melengkapi secara bertingkat (dari sifat lahiriah hingga batiniah) dan penuh rahasia.109 2.3.1. Faham Kebudayaan Jawa di Tengah Perubahan Sejak jaman kuno hingga sekarang kebudayaan Jawa sendiri memiliki wujud dan hasil yang senantiasa berkembang. Hal itu disebabkan oleh berbagai pengaruh dari dalam dan dari luar masyarakatnya yang bersifat langsung kelihatan (fisik) maupun tidak langsung kelihatan (non fisik). Dalam kajian Koentjaraningrat ada dua sisi yang berpengaruh dalam rangkaian peristiwa perkembangan kebudayaan faham Jawa. Pengaruh pertama adalah kedudukan alam maupun keadaannya, seperti tempat tinggal penduduk Jawa yang terletak di jajaran kepulauan laut wilayah katulistiwa dengan masyarakat pesisir berpencaharian nelayan ataupun dagang, dan masyarakat pedalaman yang berpencaharian petani dengan tanah subur di lingkungan pegunungan maupun gunung-gunung berapi. Keadaan alam ini memiliki pengaruh pada keper-cayaan orang-orang Jawa terhadap kuasa109 Niels Mulder, Individual and Society in Java: A Cultural Analysis (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), 5-6. 63 kuasa roh-roh maupun kekuatan-kekuatan alam yang diyakini memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia.110 Misalnya kepercayaan tentang Déwi Sri terkait kesuburan di tengah masyarakat petani yang ada di Jawa. Nama lain dari Dewi Laksmi yang dikenal sebagai lambang kesuburan keturunan bagi manusia bersama dengan pasangannya Sang Dewa Wisnu tersebut diyakini juga menjadi lambang kekuatan alam atas kesuburan tanah dan pertanian dalam wujud bulir-bulir padi yang bernas, sebagai sarana kesejahteraan atau keselamatan manusia dan alam.111 Kepercayaan itu terdapat kesejajaran dengan kepercayaan terhadap Déwi Lanjar, sang penguasa Laut Utara (Laut Jawa) yang memiliki hubungan dengan dunia perdagangan dan kemakmuran berupa kekayaan di tengah kepercayaan masyarakat pesisir. Selain kesuburan dan kemakmuran, ada pula kepercayaan tentang Kanjêng Ratu Kidûl (Déwi Gilang Kêncânâ), Sang Ratu Penguasa Laut Selatan (Samudra Hindia) yang sosoknya sering diwakili sang Maha Patih bernama Déwi Sri Kaditâ (Nyai Rârâ Kidûl) dalam menyatakan diri pada orang-orang dan rajaraja Jawa. Sosok-sosok itu dipercaya berhubungan dengan perlindungan, keamanan, dan ketentraman kerajaan di Jawa.112 Pokok pengertian tentang kepercayaan terhadap Sang Ratu itu juga mirip dengan kepercayaan terhadap Nyai Endang Jwiri alias Nyai Selâ Gilang, Sang Penguasa Gunung 110 Koentjoroningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 35-47. Philip van Akkeren, Dewi Sri dan Kristus: Sebuah Kajian Tentang Gereja Pribumi di Jawa Timur (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 16-18. 112 Ch.Masroer Jb., The History of Java: Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa (Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2004), 21. 111 64 Merapi yang diyakini memiliki hubungan dengan kekuasaan, keamanan, dan kejayaan raja Jawa Mataram beserta kerajaannya sehingga sering diberikan sesaji gunung.113 Adapun pengaruh yang kedua adalah masuknya kebudayaan-kebudayaan besar dari luar, yaitu kebudayaan Asia Selatan dari India melalui agama Hindu dan Buddha, kebudayaan Timur Tengah dari Arab melalui agama Islam, serta kebudayaan Barat dari Eropa melalui agama Kristen. Singkatnya, pengaruh kebudayaan-kebudayaan besar dari luar tersebut terjelma di dalam pandangan-pandangan mistik Jawa yang hidup secara kuat di lingkungan kāratôn (kaum priyayi), kehidupan kaum abangan dan santri dalam menjalani tata aturan agama (syari’at), serta ajaran-ajaran kêbatinan sebagai filosofi sekaligus dasar etika yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa.114 Dengan kata lain, wujud perkembangan faham Jawa di tengah perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya itu tidak bisa hilang, bahkan akhirnya terjema dalam tiga wujud kelompok perjumpaan budaya, yaitu priyayi, santri, dan abangan. Kenyataan itu dibuktikan dengan sikap ketiga kelompok golongan tadi dalam memeluk agama-agama yang secara resmi diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katholik, dan Kristen Protestan. Meskipun mereka masing-masing memiliki pilihan dalam menerima agama-agama resmi tadi, namun baik di kota 113 114 Soetomo Siswokartono, Filsafat Jawa (Semarang: Kanthil, 2010), 142. Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, 3-4, 30-64. 65 apalagi di desa masih banyak di antara mereka yang tetap melaksanakan rupa-rupa slamêtan, sebagai ungkapan jatidiri manusia (Wông) Jâwâ.115 Walaupun menurut Koentjaraningrat dalam sisi pengaruh yang kedua tersebut memiliki dampak negatif, khususnya karena proses penjajahan atau kolonialisasi oleh Bangsa Barat, namun terdapat pula akibat yang positif. Selain pengenalan terhadap dunia ekonomi industri dan pendidikan modern, kebudayaan Barat juga memberikan pengaruh terhadap munculnya ajaran kebatinan yang bernama Pangestu. Ajaran ini merupakan ajaran dari Raden Sunarto Mertowardojo yang memadukan faham Kêjawèn dengan ajaran Trinitas di dalam Kekeristenan.116 Singkatnya, faham budaya Jawa di tengah perubahan masyarakat sejak jaman kuno hingga sekarang memang mengalami perkembangan sebagai dampak perjumpaan dengan dunia kehidupan yang merupakan konteks, baik dengan alam maupun budaya luar. Namun, semua perkembangan yang terjadi itu merupakan penampilan luar yang dihasilkan dari penggunaan cara pencam-puran nilai-nilai kehidupan luar yang diterima karena dianggap sejajar dengan nilai-nilai kehidupan diri orang Jawa sendiri. Tanpa harus terlalu banyak mempertimbangkan kemurnian teologis, para kaum Jawa cenderung mengacu pada tata jalinan etika yang sama, maupun pada pandangan-pandangan tentang hubungan pribadi dengan masyarakat yang 115 Marbangun Hardjowirogo, Manusia Jawa (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), 17- 25. 116 Suwarno Imam S., Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 50-52. 66 dapat diperbandingkan dan mampu dipahami secara penuh dengan khasanah keberadaan Kêjawén.117 Tampilan luar yang menjadi wujud berkembangan di atas tidak berarti mengubah inti faham budaya Jawa. Meskipun pada perkembangan saat ini ada tiga kelompok golongan masyarakat yang terbingkai pula dalam penganut agama-agama resmi dari luar, akan tetapi dengan kuat ataupun longgar mereka tetap memperlihatkan kehidupan yang diistilahkan oleh Mulder sebagai “kejawaan” mereka.118 Wujud “kejawaan” itu berupa perilaku-perilaku pribadi maupun bermasyarakat dalam bentuk tindakan dan karya harmoni ataupun upacara-upacara slamêtan sebagai ungkapan kepercayaan sesuai dengan cara pandang mereka. Cara bertindak pribadi ataupun masyarakat Jawa itu disebut pula dengan istilah perilaku hybrid interconnectedness, yaitu tindakan yang dihasilkan dari persilangan untuk mengatasi ketegangan karena berbagai nilai kebudayaan dan peradaban berbeda yang saling bertemu.119 2.3.2. Perwujudan Faham Kebudayaan Jawa Kenyataan perkembangan faham Jawa di atas memiliki beberapa perwujudan. Pertama, sikap dan tata perilaku orang Jawa. Ada banyak sikap dan tata perilaku orang Jawa dan selalu sarat dengan makna keselarasan. Beberapa di antaranya yang sering dinampakkan adalah têpâ salirâ (segala 117 Mulder, Individual and Society in Java, 4. Mulder, Individual and Society in Java, 1. 119 Sondong Mandali, Ngelmu Urip: Bawarasa Kawruh Kejawen (Semarang: Yayasan Sekar Jagad, 2010), 28. 118 67 sesuatu diterapkan pada diri pribadi), êmpan papan (segala sesuatu disesuaikan dengan tempatnya), narimâ ìng pandûm (menerima segala sesuatu yang menjadi bagian hidup), pasrah sumarah (berserah dan mempercayakan hidup sepenuhnya), sabar (tidak gampang marah dan bertindak sembrono), âjâ duméh (jangan mentang-mentang), samadyâ (jangan berlebihan berbuat segala sesuatu). Semua itu harus dilakukan dengan sikap rasa penuh hormat (ngajéni) kepada sesama dan dirinya karena elìng (selalu sadar dalam segala hal) dan waspâdâ (hati-hati dan penuh pertimbangan cermat). Tindakan etis orang Jawa itu oleh Mulder disebut tingkah laku perorangan sebagai moral yang didasar-kan pada sikap nrimâ, sabar, wâspâdâ, elìng, andhap asôr, dan prasâjâ. Kemampuan di dalam mewujudkan tindakan itu dianggap perbuatan hidup yang benar. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika itu merupakan penyimpangan atau perbuatan hidup yang salah, mengganggu dan merusak tata keseimbangan alam dan kehidupan dunia.120 Tanpa sikap rasa hormat maka perbuatan seseorang akan menimbulkan berbagai macam kekacauan dan kerusakan.121 Kedua, pandangan diri orang Jawa tentang manusia dan keyakinannya akan Tuhan. Oleh orang Jawa, Tuhan disebut Sang Hyang, atau Gûsti (Tuan), Pangeran (Papan pangéngéran: tempat mengabdi dan berbakti). Tuhan itu sumber mula dan tujuan akhir dari segala sesuatu yang tercipta (sangkan paranìng dumadi), termasuk manusia. PribadiNya adalah Maha 120 Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Jakarta: Gramedia, 1984), 22-23. 121 Fachry Ali, Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern (Jakarta: Gramedia, 1986), 16. 68 Tinggi, Maha Agung, dan Maha Mulia, sehingga dengan pengetahuan manusia biasa tidak bisa atau sulit dipahami secara tepat, namun keberadaanNya dapat dirasakan (Gûsti tan kênâ kinirâ-kirâ, aywâ tan kenâ kinâyâ ngâpâ, ngìng bisâ rinâsâ: Tuhan tidak bisa direka-reka dengan pikiran manusia juga tidak bisa diupamakan atau disamakan dengan apapun, namun kenyataan akan keberadaanNya bisa dirasakan). Kenyataan itu bisa ada di mana-mana (Gûsti iku dumunûng ìng ngêndi papan, anéng sirâ ugâ ânâ Gûsti: Tuhan itu ada di mana pun tempatnya melalui daya kekuatan yang bersifat animis maupun dinamis, di dalam dirimu (manusia) juga ada Tuhan). Pandangan yang diungkapkan oleh Yana pada dasarnya menegaskan pula penjelasan Masroer tentang kepercayaan asli dan khas orang Jawa, yaitu agama bercorak animis dan dinamis yang dipandang menjadi penyebab mistisme Jawa berdasarkan gagasan pokok mikro kosmos dan makro kosmos. Dalam penjelasan itu, Gûsti yang merupakan kenyataan mutlak tanpa batas cenderung dihayati secara imanen dalam wujud kehadiran, bahkan bisa melebur dalam diri manusia, demikian juga dalam wujud roh-roh, makhluk-makhluk halus, maupun benda-benda kasat mata dengan kekuatan gaib.122 Dengan rasa itulah pemahaman Tuhan yang tidak mudah menjadi unik. Tuhan yang tak tersentuh dan seakan jauh, tetapi pada satu sisi terasa sangat dekat; bahkan menyatu dalam kehidupan diri manusia (Gûsti iku adôh tanpâ wangénan, cêdhak tanpâ senggôlan: Tuhan itu jauh, tetapi tidak berjarak; namun dekat, meski tidak bisa tersentuh). Kenyataan 122 Masroer, The History of Java, 19-20. 69 keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana dan bisa dirasa secara demikian unik itu dimengerti pula sebagai Hyang Maha Tahu (Gûsti tan nate klilapan marang jalmâ titah, Gûsti Mâhâ Pìrsâ. Panjenengane ora sare: Tuhan tidak pernah lepas perhatian kepada makhluk ciptaanNya, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tidak tertidur atau lengah). Inti dari kepercayaan itu adalah bahwa Tuhan Maha Kuasa (Hyang Wenang/Kewâsâ), Sang Pencipta jagad raya beserta kehidupan, yang keberadaanNya dekat dengan manusia itu merupakan Pemilik, Sumber dan Kiblat, serta Pemelihara dan Pengatur seluruh ciptaan (Pangréhìng jagad serta Pangrêksanìng titah), termasuk manusia (réh-réhan) yang harus menurut (nggugu) dan taat (mituhu) tanpa menentang (tan kenâ suwâlâ) terhadap semua ketetapanNya agar beroleh kehidupan yang selamat secara lahir maupun batin dalam kesatuan jiwanya dengan Tuhan sebagai pengetahuan tertinggi dan sempurna (kawrûh jati). Ketiga, bentuk kemasyarakatan orang Jawa yang saling berjalinan di dalam tata susunan kehidupan bersama. Pola kemasyarakatan itu merupakan penerapan dari pokok pengertian keselarasan jagad gêdhe dengan jagad cilìk, yang terjelma dalam kasta dan sebutannya, yaitu Gûsti (tuan, untuk raja) ataupun bāndârâ (untuk bangsawan) dan kawulâ (abdi), priyayi (bangsawan) dan abdi (hamba), wông luhur/gêdhe (golongan atas atau terkemuka) dan wông cilìk (golongan rendah jelata), dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan tersebut menunjukkan kedudukan dan peran dari tiap-tiap golongan yang memiliki keterkaitan penting sebagai penata (pangréh) yang lekat dengan lambang kêrìs (piranti senjata atau pusaka, sekaligus lambang 70 kekuatan, kekuasaan, ataupun pemerintah), dan pelaksana (réh-réhan) yang lekat dengan pacûl (piranti bekerja, sekaligus lambang rakyat, hamba, ataupun pekerja) sebagai upaya pelestarian tatanan bagi kelangsungan hidup bersama. Pemahaman lambang pemimpin dan rakyat semakin jelas dengan keterangan Suwardi Endraswara, bahwa pada masa lalu kêrìs memang dijadikan lambang sekaligus keabsahan seorang raja dan pembesar kerajaan, serta para kesatria yang memberikan kesan kebesaran dan keagungan. Adapun alat pertanian menjadi lambang rakyat.123 Keterkaitan penting antara golongan satu dengan golongan yang lainnya itu dilakukan dengan suatu cara hubungan berdasarkan tataran-tataran dalam “unggah-unggûh” yang terdapat pada perilaku dan bahasa Jawa. Tataran-tataran hubungan itu merupakan tata aturan dan diterima dalam bentuk keyakinan-keyakinan sebagai pêpêsthi (ketetapan) atau kārsane Gûsti (kehendak Tuhan) yang harus dijalani dengan sikap narimâ ìng pandûm dan ngajéni secara penuh (erìng: segan). Sikap tersebut menjadi pendorong bagi orang Jawa untuk selalu menyesuaikan dirinya dengan jalan têpâ sālirâ dan êmpan papan, agar selalu ada kelestarian (slamêt). Pokok pengertian tersebut bisa dilihat dalam kepemimpinan para raja Jawa yang merupakan lambang keberadaan Tuhan dengan sebutan titisan dewa (Bāthârâ) ataupun Gûsti dengan rakyat yang diperintah agar negara dapat tetap berdiri dan sejahtera. 123 Suwardi Endraswara, Buku Pintar Budaya Jawa: Mutiara Adiluhung Orang Jawa (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), 315. 71 Keempat, tata bangunan rumah dan kāratôn yang menjadi pusat sekaligus gambaran keselarasan yang antara jagad gêdhe dengan jagad cilìk. Seperti tepat di tengah kāratôn Jawa Mataram selalu ada gêdhông (bangunan) sitinggìl (siti inggil: permukaan tanah atau tempat dan ruang yang paling tinggi) sebagai tempat raja melakukan sāmádi (mengheningkan cipta) untuk berhubungan dan beroleh petunjuk (wangsìt) maupun daya kemampuan (sakti) dari Sang Hyang dalam menjalankan pemerintahan. Depan gêdhông sitinggìl ada tempat sewâkâ (menghadap) pada raja sekaligus tempat pertemuan raja dengan para pejabat bawahannya yang disebut bale agûng untuk merembuk pemerintahan dan menyatakan petunjuk dari Tuhan agar dijalankan oleh rakyat ataupun pengikutnya di seluruh penjuru negeri dengan lambang wilayah kekuasaan dalam bangunan-bangunan rumah yang dirancang menggunakan pokok pengertian kiblat papat, limâ pancêr (keempat penjuru, yang kelima pusatnya) alias empat arah mata penjuru dunia di sekeliling istana yang adalah pusatnya. Pokok pengertian itu oleh Durkheim dan Mauss diistilah mâncâpat, yaitu pola pengelompokan sekaligus penggabungan dengan beberapa daerah kekuasaan untuk mengatur kepentingan bersama.124 Pola demikian itu sebagai gambaran letak kedudukan pada keempat penjuru mata angin dengan satu tempat di tengah yang merupakan pusatnya.125 Semua ditata sedemikian rupa sebagai keseimbangan bagi keseluruhan hidup. Lebih unik lagi falsafah kibtat papat limâ pancêr sebagai keseimbangan kehidupan 124 125 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, 431-432. van Akkeren, Dewi Sri dan Kristus, 9-13. 72 semesta tersebut juga terjelma dalam warna dan corak beserta perpaduannya pada kain atau pakaian, yang melambangkan unsur-unsur dan sifat-sifat alam di dalam kehidupan.126 Kelima, karya seni khususnya dari lingkup kāratôn yang tidak bisa dilepaskan pula dari makna keserasian kehidupan di tengah masyarakat Jawa. Ada beberapa karya seni yang secara kuat mengungkapkan pandangan kehidupan masyarakat Jawa, yaitu wayang, bêksâ (tari), gêndhìng (musik), dan senjata pusaka. Wayang artinya bayangan, yaitu seni pertunjukan cerminan (bayangan) kehidupan dalam bentuk kisah sandiwara yang memberikan wêjangan etika agar manusia hidup serasi dengan sesama dan alam lingkungannya melalui peraga tiruan ataupun oleh orang secara langsung sebagai para lakôn (pelaku). Dalam filsafat Jawa, wayang itu merupakan piwucal (pengajaran) tentang kehidupan manusia yang dibagi dalam tiga bagian penting (pathêt), yaitu pathêt nêm, pathêt sângâ, pathêt manyurâ yang melambangkan tahapan hidup dari masa anak-anak, muda dan dewasa, hingga tua.127 Berikutnya adalah bêksâ (tari), yaitu seni pertunjukkan gerak tubuh yang terarah penuh makna dalam irama secara harmoni untuk mengungkapkan suatu kiasan alam dan kehidupan. Tari sebagai salah satu bentuk seni pertunjukkan memiliki tiga kegunaan utama, yaitu untuk: (1) sarana ritual, (2) ungkapan pribadi bagi kesenangan atau hiburan, dan (3) pengungkapan rasa yang bermakna keindahan. Di 126 Apika Nurani Sulistyati, “Kiblat Papat Lima Pancer: Sebagai Media Refleksi dalam Wujud Karya Tekstil,” (Skripsi, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2009), 4-6, 17, 25. 127 Soetomo, Filsafat Jawa, 83-84. 73 lingkungan kehidupan adat masyarakat Jawa tari lebih bersifat ritual, sehingga dipercaya memiliki sisi keramat dan pelaksanaannya selalu berhubungan dengan upacara kepercayaan.128 Misalnya Tari Wayang Maha Baratha dan Tari Ramayana untuk pemujaan Dewa Wishnu yang menjelma dalam diri raja berkuasa, Tari Bêdâyâ dan Tari Srimpi untuk menghadirkan sosok kekuatan adikodrat (yaitu: Kanjêng Ratu Kidûl) pelindung kerajaan beserta raja dan segenap ketentraman rakyatnya, Tari Gambyông untuk menyambut tamu kehormatan raja, Tari Tayûb untuk upacara pernikahan maupun upacara pertanian, dan lain sebagainya. Seni gerak itu umumnya juga tidak terpisahkan dari seperangakat alat musik (gamêlan: peralatan musik yang dimainkan secara harmoni) beserta dengan nyanyian (kidûng) pengiringnya. Suryo Pugiarto menjelaskan bahwa gamêlan dan têmbang (kidûng) merupakan musik (gêndhìng) Jawa yang selalu serempak berpadu sebagai keselarasan dalam laras (irama) pelôg (nada mayor Jawa) maupun laras slendro (nada minor Jawa).129 Menurut pandangan mistik ter-dapat kekuatan “supra-natual” di dalam tarian tertentu maupun gamêlan dan kidûng yang dilantunkan, sehingga tidak boleh diperlakukan dan dimainkan secara sembarangan. Irama gamêlan maupun kidûng itu merupakan mantra sastra (suara yang memiliki daya kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap manusia dan kehidupan sekitarnya apabila dilantunkan).130 Selain itu ada 128 R. M. Soedarsono, Seni Pertunjukkan Indonesia di Era Globalisasi (Yogyakarta: Gadah Mada University Press, 2002), 123-126, 140-148. 129 Suryo Pugiarto, Sugeng Dambaan Masyarakat Jawa Berwawasan Integral: Sebuah Langkah Awal dalam Memperteguh Jati Diri (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), 37. 130 Sondong, Ngelmu Urip, 122-124. 74 senjata pusaka, yaitu piranti untuk membela diri ataupun melumpuh musuh. Di antara senjata yang banyak dimiliki oleh orang Jawa, kêrìs merupakan salah satu senjata andalan (piyandêl), yang dipandang menjadi lambang kewibawaan, kekuatan atau kesaktian, kekuasaan, dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan orang yang cocok menyandangnya atau menjadi pasangannya, seperti ungkapan bersatunya kêrìs itu sendiri dengan wrângkâ (wadah kêrìs), yaitu curigâ manjíng wrângkâ yang melambangkan keserasian hidup antara jagad gêdhe dengan jagad cilìk. Kêrìs dan wrângkâ merupakan satu kesatuan yang kegunaannya saling berhubungan satu sama lain. Keduanya memiliki makna lambang hubungan erat dan menyatu untuk mencapai keharmonisan hidup di dunia, yang disejajarkan dengan pokok pengertian manunggalìng kawulâ lan Gûsti.131 Kawula atau manusia digambarkan dengan wrângkâ, adapun Gusti atau raja digambarkan dengan kêrìs yang dipercaya memiliki daya sakti dan mesti bertempat di dalam wrângkâ.132 Karena itu, masing-masing harus saling menghormati dan tahu diri untuk melakukan bagian pekerjaan serta tugasnya. Keenam adalah upacara kepercayaan yang telah menjadi adat di tengah kehidupan masyarakat Jawa. Upacara itu dilakukan untuk memuja roh-roh yang menjadi wujud kekuatan akan keberadaan Tuhan dan diyakini memiliki pengaruh pada kesejahteraan hidup manusia. Istilah Jawa untuk pemujaan itu disebut slamêtan, yang pada pokoknya meliputi beberapa bentuk. 131 132 Fachry, Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, 30-31. Endraswara, Buku Pintar Budaya Jawa, 321-322. 75 a. Pertama slamêtan tolak bâlâ yang diadakan untuk menangkal bencana alam maupun wabah (pagêblûg), seperti: gempa, gunung meletus, banjir, hama, penyakit, termasuk gangguan roh jahat, dan lain sebagainya. b. Kedua slamêtan ruwatan yang dilakukan untuk membuang kesialan, nasib buruk, maupun kutukan, seperti: ngêthôk kuncûng dan ngêthôk bajang (memotong rambut panjang kuncir atau rambut panjang gimbal agar seorang anak tidak sering sakit-sakitan), metri desâ (bersìh desâ: memelihara kebersihan desa agar warga tidak kena pagêblûg, ataupun gangguan-gangguan lain), dan lain sebagainya. c. Ketiga slamêtan di masa tahap kehidupan seseorang, seperti: nyidham (tanda keberadaan jabang bayi di dalam kandungan), mandhêkìng (usia kandungan tiga bulan dan lima bulan), tingkêban (usia kandungan tujuh bulan), brôkôhan (kelahiran), muyén (mêlékan: tidak tidur untuk menjaga bayi yang baru lahir dari gangguan Si Kâlâ, selama sāpasar), puputan (hilangnya tali puser sang bayi pada usia sāpasar: lima hari, dan dilakukan kêrìk: cukur kêrôk rambut bayi), jênêngan atau selapanan (memberi nama bayi pada usia sālapan: tigapuluh lima hari), têdhak siti (saat bayi diturunkan ke tanah pada usia tujuh bulan untuk belajar berjalan), têtakan (remaja laki-laki akil balik yang ditandai dengan sunat) atau têtêsan (remaja perempuan akil balik yang ditandai dengan sunat atau pangûr: meratakan gigi dengan tatah dan batu ungkal), kumbôkarnan (persiapan menikah bagi calon mempelai 76 pria) atau midôdari (persiapan menikah bagi calon mempelai wanita), rabi (menikah), gêblagan (kematian) yang terdiri dari nêlûngdinâ (sûr tanah: peringatan hari ketiga pada orang yang meninggal), mitûngdinâ (peringatan hari ketujuh orang yang meninggal), matangpulûhdinâ (peringatan hari keempatpuluh orang yang meninggal), nyatûsdinâ (peringantan hari keseratus orang yang meninggal), mêndhak pisan (peringatan satu tahun orang yang meninggal), mêndhak pindho (ndhagêl: peringatan dua tahun orang yang meninggal), nguwisi (menyudahi: peringatan orang yang meninggal kurang lebih seribu hari (nyéwu dinâ), karena arwahnya dianggap telah menjadi sempurna dan kembali kepada Tuhan). d. Keempat slamêtan untuk kehidupan pencaharian yang dilakukan agar sumber perekonomian tetap terjaga dan tidak kekurangan, seperti: Labûh (menggarap sawah mulai dari mengolah tanah, menabur benih padi sampai menanam dan merawatnya), wiwìt (memanen padi yang dihasil-kan dari kesuburan tanah olahan), tumpak lumbûng (menaikan untaian-untaian padi yang dipanen dan sudah dikeringkan ke dalam lumbung untuk disimpan sebagai persediaan bahan pangan). Selain itu ada pula slamêtan sêdêkah bumi (memberi sesaji pada Hyang, Sang Penguasa bumi atau tanah agar selalu memberikan kesuburan tanah dan pertanian), slamêtan sêdêkah laût (memberi sesaji pada Hyang, Sang Penguasa laut agar memberi kelimpahan hasil laut). 77 e. Kelima slamêtan harian yang dilakukan untuk menghormati dan menghindari gangguan pada anggota keluarga oleh roh-roh sêsêpûh, sekaligus mendapatkan perlindungan ataupun pertolongan dari mereka. Wujud upacaranya adalah memberi sesaji makanan yang dikhususkan (mintâ dhaharan) yang diambil dari sedikit olahan makanan untuk keluarga pada hari itu, dan diletakkan di dalam kamar atau ruangan (sênthông) yang sering dipakai oleh sesepuh sewaktu masih hidup sambil memanjatkan doa atau permohonan. f. Keenam slamêtan khajatan kāratôn yang dilakukan untuk mengkukuhkan kekuasaan kerajaan, seperti: tingalan ndalêm (peringatan kelahiran yang mulia raja), jumênêngan ndalêm (peneguhan dan peringatan naik tahta yang mulia raja), jamasan (pembasuhan) pusaka kerajaan, surânan (Tahun Baru Jawa dalam nuansa Islam), grêbêg gunungan (sedekah kāratôn bagi rakyat), dan lain sebagainya. 2.3.3. Tata Susunan Upacara Kepercayaan Jawa Berbagai macam upacara di atas memiliki pokok bagian penting yang pada umumnya sama, yaitu: pemberian sesaji dengan rapal rumusan mantra kepada roh-roh leluhur ataupun Sang Hyang. Sesaji itu sendiri sebenarnya adalah wujud dari bantên (korban atau persembahan), berupa makhluk hidup yang disembelih ataupun makanan yang diolah, maupun benda-benda tertentu yang dipercaya diinginkan oleh sang sosok adikodrat. Korban itu dimaksud-kan sebagai sarana pemujaan dan ucapan syukur, namun juga bisa 78 sebagai sarana pengganti atau penebus kesalahan atau penyimpangan disengaja maupun tidak sengaja terhadap ketentuan hidup yang telah digariskan oleh Sang Hyang sehingga membatalkan petaka yang bakal ditimbulkan. Agar semua sarana itu diterima, perlu dihantarkan melalui pengucapan mantra. Karena penghantarnya adalah mantra, maka diangap tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mantra itu harus diucapkan oleh orang mumpuni dalam berhubungan dengan pribadi maha agung dan berkuasa itu. Contohnya pemberian sesaji ketika hendak panen padi (wiwít) berupa nasi tumpeng putih kecil dengan puncak cabai merah (lômbôk abang) dan bawang merah (brambang) ditusuk jadi satu. Ada pula air putih dalam kêndhi dan íngkûng (ayam yang disembelih dimasak utuh), ditambah telur rebus dan pelas kangsén (larva lebah madu), atau aneka masakan lainnya. Persembahan itu dibagi menjadi lima bagian untuk diletakkan di keempat sudut sawah (sebagai lambang hormat pada empat saudara yang tak terlihat, yaitu sêdulûr kawah/ketuban, ari-ari/placenta, gêtíh/darah, pusêr/ usus pusar; turunan dari pokok pengertian kiblat papat limâ pancêr dengan berbagai lambang serta makna keseimbangan alam semesta), dan yang satu lagi di tengah depan sesepuh pemimpin slamêtan yang membawa kembang dan membakar dupa kemenyan sambil merapalkan mantra pujian dan syukur kepada sang maha agung yang sering dikenal dengan sebutan Déwi Sri, karena telah memberi keselamatan tanaman padi hingga dapat dituai. Akhir menghantarkan sesaji itu, sang sesepuh menuangkan air dari kêndhi ke atas tanaman padi dan memotong beberapa untai tanaman rumpun siap 79 panen itu menjadi dua ikatan sebagai pêngantén padi yang melambangkan Déwi Sri dan Radén Sri Sadânâ. Lambang itu kemudian diserahkan kepada pemilik sawah supaya diarak dan ditempatkan (disimpan) di lumbung, yang akhirnya digunakan sebagai bagian dari calon bibit di waktu selanjutnya. Cara bersesaji tersebut pada intinya sama dengan aneka upacara slamêtan yang lainnya. Hanya isi mantra yang diucap-kanlah yang berbeda karena maksud dan tujuan masing-masing. Selesai melafalkan mantra penghantar sesaji disampaikanlah ujûb, yaitu maksud dan tujuan slamêtan yang diselenggarakan. Agar ujûb itu dapat mengena dengan baik dalam pemahaman khalayak yang hadir, maka yang menyampaikan biasanya juga sesepuh. Sebab maksud dan tujuan itu tergambar dalam lambang-lambang yang disebut ubârampe (kelengkapan persyaratan). Seperti dalam upacara wiwít tadi, sesepuh akan mengartikan lambang dari nasi tumpeng putih dengan puncak brambang dan lômbôk abang. Nasi tumpeng putih adalah lambang gunung tempat maha tinggi serta bersemayamnya Sang Hyang yang disembah, sekaligus sebagai lambang alam dan kehidupan maupun asal usul segala ciptaan (sangkang paraning dumadi), yaitu jagad gêdhe dan jagad cilík yang dilambangkan juga dengan gambar gunungan atau kayôn dalam peraga wayang pûrwâ (wayang kulit) yang memberi kehidupan dan berkat kesejahteraan.133 Alamlah yang menjadi kesuburan serta tempat tumbuh tanaman kebutuhan pokok. Karena itu setiap orang harus ingat muliakan Sang Pencipta dan 133 Agus Purwoko, Gunungan: Nilai-Nilai Filsafat Jawa (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 26, 30-31. 80 bersyukur atas kemurahanNya dengan menjaga serta mendayagunakan alam secara seimbang menurut ketentuan hidup bersama. Brambang serta lômbôk abang adalah panah yang melambangkan manah (hati) sebagai pusat cipta, rasa, dan karsa atau tempat têtimbangan (pertimbangan nalar dan budi) dalam ungkapan permainan singkatan di akhir suku kata: bram+ mbang (animbang). Kedua jenis bumbu itu sering diringkas hanya lômbôk abang saja sebagai gambaran kêris yang melambangkan makna keutuhan pribadi manusia yang harus tahu dan dapat menempatkan diri dalam tata kehidupan semesta.134 Lambang-lambang itu berisi peringatan dan ajaran supaya manusia dapat menjaga dan mendayagunakan kehidupan beserta hasilnya secara seimbang dengan menggunakan cipta, rasa, dan karsa (pertimbangan batin) dalam karya kebenaran bagi keseimbangan atau kesejahteraan bersama. Adapun íngkûng dan air putih yang dikucurkan pada rumpun padi merupakan lambang tangan menyembah atau sikap dan tindakan berdoa (manêkûng, sebagaimana kedua sayap íngkûng (singkatan kata Híngsûn Hamanêkûng: aku memusatkan keinginan dengan bersembah) yang dirapatkan jadi satu) sebagai dasar bekerja dan akhirnya layak merasa tenang (sirêp: hilang kegundahan dalam penantian hasil karya, dan menjadi asrêp: dingin dan tenang dengan lambang siraman air putih dari kêndhi) karena akhirnya beroleh hasil. Pesan yang disampaikan dari lambang-lambang itu adalah manusia tidak boleh lepas dan melupakan Tuhan, Sumber kehidupan di dalam semua karya tindakannya melalui doa harapan sehingga beroleh 134 Ragil Pamungkas, Mengenal Keris: Senjata Magis Masyarakat Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2007), 44-45. 81 hasil dan ketenangan. Demikian pula dengan telur rebus dan pelas kangsén. Keduanya merupakan satu kesatuan makna. Lambang telur bermakna wiji dadi (benih utuh berisi), sama dengan biji padi (las) siap panen yang antêpe (bobotnya) penuh berisi (kang ânâ isén-isénane) dalam lambang permainan kata berwujud makanan: pe + las dan kang + sén. Sebagai wiji dadi, maka bulir-bulir itu merupakan benih yang hidup, sekaligus memberikan kehidupan. Ajaran dari lambang-lambang itu adalah bahwa dengan berkat pemberian Tuhan Maha Murah dalam karya pekerjaan dan hasilnya, pada akhirnya demi kelestarian (keseimbangan yang berkesinambungan) hidup maka manusia harus dapat mewujudkan keutamaan dengan menunjukkan isi kemampuan hidupnya yang berguna bagi sesamaan dan alam, seperti butir telur yang bisa menetas (nêtês) dan bulir padi bernas (mêntês). Tahap pelaksanaan upacara slamêtan selanjutnya adalah pemanjatan doa permohonan berkat keselamatan kepada Tuhan atau sang sosok adikodrat. Umumnya sesepuh akan memanjatkan doa bersifat umum, seperti kerukunan keluarga maupun keluarga dengan masyarakat. Kesehatan keluarga agar giat bekerja sehingga beroleh penghasilan yang cukup, dan terhindar dari petaka. Demikian pula untuk kelestarian keluarga dengan anak dan keturunan yang banyak, mereka selalu menghormati orang tua, sesepuh, dan leluhur. Pada akhirnya seisi keluarga supaya selalu ingat pada Gûsti Kang Akaryâ Uríp (Tuhan yang menjadikan hidup dan kehidupan). Seluruh doa itu arahnya pada keseimbangan sebagai keselamatan dalam 82 kehidupan manusia, yang disahut oleh keluarga empunya sawah maupun segenap hadirin dengan kata: kasêmbadanânâ (terkabullah), atau amin. Pada akhirnya, jalannya upacara slamêtan ditutup dengan membagi makanan slamêtan (bancaan) untuk dinikmati bersama para hadirin maupun orang-orang di sekitar tempat tinggal sang empunya kerja, atau dibawa pulang ke rumah masing-masing dengan gembira bersama. Bancaan yang sering disebut juga dengan pajatan atau kenduri itu berisikan masakan nasi putih, lauk (telur rebus, ikan asin (gêréh) péthék, daging ayam), sayuran kuluban (dedaunan hijau yang direbus, seperti bayam atau kangkung, kacang panjang beserta kecambah kacang hijau) dibumbu gudangan (sambal kelapa yang dicampur rata dengan kuluban), dan aneka jajan pasar. Apabila dimakan bersama di tempat sang empunya kerja, maka bancaan tadi dihidangkan bersama dengan banyu tâwâ (air murni atau air putih tanpa rasa). Namun, upacara kepercayaan tersebut dipercaya akan dapat dialami daya pengaruhnya bila penyelenggara juga menyertainya dengan tindakan (laku) sesuai ketentuan yang disampaikan, baik dalam bentuk pitutûr (petunjuk) lugas maupun gugôn tuhôn (ajaran dalam bentuk mitos sebagai lambang-lambang agar digugu dan dituhôni). Dalam contoh lain, ketika orang yang telah melakukan upacara slamêtan pada masa nyidham tidak boleh menyematkan bunga maupun sisir di kepala, ataupun mengenakan subang dan cincin. Semua itu dianggap dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan kelahiran bayi pada nantinya. Selain itu juga 83 dilarang makan makanan dari daging sungsang (hewan yang lahirnya keluar kakinya lebih dulu) dan daging yang menimbulkan rasa panas, daging ikan pemakan daging dan buas, maupun tidak boleh makan buah-buahan yang berakibat pada rasa yang sama di tubuh. Ketika makan calon ibu yang sedang mengandung muda itu tidak boleh berada di depan atau di tengah pintu, dilarang duduk di lumpang maupun alu (antan), serta cara makan dengan piring tidak boleh disânggâ (ditopang) tangan supaya calon bayi tidak dimangsa oleh si Kâlâ (Bāthârâ Kâlâ). Sebaliknya, calon ibu itu harus rajin minum ramuan cabe lêmpuyang tiap delapan hari sekali pada hari Rabu atau Sabtu, cuci tangan dan kaki dengan air yang dicampur garam sewaktu hendak tidur sambil melantunkan rapal pengusir sang Kala:135 Singgah, singgah, Kâlâ singgah! Kang abuntût, kang awulu, kang ajâthâ, kang asiûng, pâdhâ sirâ suminggahâ! Âjâ wurûk sudi gawe! Aku wûs wêrûh ajal kamulanirâ. (Menyingkirlah, menyingkirlah, Marabayaha menyingkirlah! Yang berekor, yang berbulu, yang berambut, dan yang bertaring, kalian semua menyingkirlah! Jangan mengganggu! Aku telah mengetahui rahasia kematianmu). Makna pitutûr dan gugôn-tuhôn itu adalah kebiasaan yang hati-hati dan waspada, tertib dan mapan, kebersihan dan sehat, baik dan sopan bagi para ibu yang sedang mengandung, khususnya di usia kandungan muda. Itu semua adalah keteraturan dan sikap untuk menjaga atau mengendalikan diri. 135 Siman Widyatmanta, Sikap Gereja Terhadap Budaya dan Adat Istiadat: Sebagai Sarana Berinteraksi dalam Kehidupan Bermasyarakat (Salatiga: BMGJ, 2007), 65-66. 84 Apabila dilanggar maka dapat membahayakan bagi keselamatan sang ibu yang sedang mengandung maupun untuk sang calon bayinya sendiri. Salah satu pokok penting lain dari tata susunan upacara kepercayaan Jawa di atas adalah bahwa banyaknya aneka bumbu dan makanan yang disertai pitutûr maupun gugôn-tuhôn itu merupakan lambang-lambang penyamar (pasêmôn), sebagai sarana komunikasi efektif bagi orang-orang Jawa untuk menyampaikan maksud penting dan dianggap memiliki nilai keramat (sakral). Inilah salah satu tradisi komunikasi orang-orang Jawa yang disebut tradisi pasêmôn.136 Makna pembelajaran itu diistilahkan oleh Ronan Hallowell sebagai kearifan kerohanian (spiritual wisdom).137 2.4. Upacara Kepercayaan Jawa Sebagai Liturgi Tata susunan upacara pemujaan masyarakat Jawa pada Tuhan dengan berbagai perwujudan di atas, memperlihatkan adanya beberapa unsur penting. Yang pertama adalah gagasan yang menjadi sumber keyakinan sebagai landasan perumusan bagi pelaksanaan upacara kepercayaan. Kedua adalah aneka lambang yang dipergunakan di tengah upacara kepercayaan untuk menyampaikan gagasan tentang pokok-pokok keyakinan beserta nilainilai kehidupan bersama dan kegunaannya. Sedangkan yang ketiga adalah keterlibatan orang-orang di dalam upacara kepercayaan yang dilaksanakan. Itulah keseluruhan tindakan hidup orang Jawa dengan kebudayaannya dalam 136 Sondong, Ngelmu Urip, 173. Ronan Hallowell, “Discernment, Ethics, and Compassion in the Cross-Cultural Practice of the Native American Sun Dance,” Re Vision: A Journal of Consciousness and Transformation 32, no. 3 (2012), 87. 137 85 mengungkapkan serta menikmati keselamatan terhubung dengan Tuhan yang memberikan ketetapan hidup serta pertolongan di tengah berbagai peristiwa atau pengalaman yang dijumpai. Unsur-unsur yang terdapat di berbagai upacara slamêtan tersebut dalam sudut pandang sosiologi agama dapat disebut juga sebagai ritual. Seperti dinyatakan White, bahwa ritual merupakan liturgi peribadahan karena dirumuskan secara khusus dengan pola-pola (susunan, penampilan, perilaku), tata cara, serta petunjuk-petunjuk bermakna tertentu. Dengan pengertian seperti itu, di dalam pelaksanaannya ada tiga pemahaman slamêtan sebagai liturgi. Yang pertama, sebagai liturgi, slamêtan merupakan ungkapan kehidupan iman umat dalam aksi atau kegiatan yang sifatnya seremonial namun juga praksis antara nilai-nilai rohani dengan jasmani, atau nilai-nilai surgawi dengan duniawi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai liturgi maka slamêtan merupakan pancaran dari penyataan Tuhan di dalam wujud dan aneka karya berkat penyelamatanNya, yang merupakan dasar bagi manusia untuk menanggapi dalam tindakan yang tertata dan terarah. Sebagai pemahaman liturgi yang ketiga, slamêtan menjadi wahana sekaligus pewujudan penghayatan akan tujuan keselamatan di dalam kehidupan manusia. Liturgi berpijak dari langkah hermeneutik sebagai penafsiran peristiwa penting di dalam pengalaman yang pernah terjadi pada kehidupan umat yang akhirnya mampu membangun sandaran baru dalam sosok yang dipandang dan diyakini bersama dapat menjadi jaminan kepastian atau 86 kemapanan hidup. Sama halnya dengan slamêtan yang dijadikan karena adanya pemaknaan suatu peristiwa penting dalam pengalaman yang dijumpai berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi pula pada masa lalu di tengah kehidupan masyarakat. Ketika ada keyakinan pada sosok yang menjadi jaminan keselamatan maka seseorang akan menjadikannya sandaran bagi kehidupan dirinya. Selain langkah hermeneutik, langkah tradisi juga menjadi dasar liturgi dengan pangkal dalil sejarah, tempat dan waktu pelaksanaan sebagaimana dibangun dan dirumuskan oleh pendiri maupun penerusnya melalui tafsir yang diterima sebagai keyakinan bersama, beserta dengan bentuk-bentuk kegiatan untuk menyampaikan maksud dan tujuan liturgi itu sendiri. Dari pemahaman tersebut, tampaknya slamêtan tidak memiliki penampilan isi yang sama persis dengan liturgi. Ketiga pangkal tolak langkah tradisi bagi liturgi memang ada, dan sebagian besar intinya punya pengertian yang serupa. Akan tetapi khusus mengenai dalil tempat dan waktu pelaksanaannya, slamêtan tidak begitu mengenal batasan terlalu khusus, seperti liturgi yang umum dikenal pada Kekristenan. Sebab di dalam slamêtan tempat pelaksanaannya cenderung langsung berhubungan dengan keberadaan alam yang telah tersedia, seperti laut, sungai, gunung, hutan, sawah, sumur, makam, batu dan pohon besar, jalan dan persimpangan-persimpangannya, rumah empunya hajad slamêtan, dan lain sebagainya. Di tempat-tempat seperti itu orang Jawa menganggap dan meyakini sudah cukup dan bisa berhubungan dengan Tuhan ataupun perwujudanNya. 87 Demikian pula dengan waktu pelaksanaannya. Dibandingkan dengan liturgi Kristen, slamêtan juga mengenal almanak tahunan, dan sudah khas. Akan tetapi kesempatan berkumpul untuk melakukan rangkaian kegiatan khusus secara teratur dalam waktu dekat atau mingguan untuk mengadakan upacara atau peribadahan dalam jumlah banyak dan bersama-sama pada umumnya tidak popular. Masyarakat Jawa memiliki hitungan minggu tersendiri, yang disebut pasar atau dibahasakan halus menjadi pêkên (dan akhirnya muncul istilah pekan). Satu pasar terdiri dari lima hari, yaitu hari Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Meskipun ada sekelompok orang Jawa menentukan salah satu hari itu untuk waktu berkumpul secara rutin guna membicarakan kepercayaan, namun pertemuan itu bukan ritual karena hanya bertukar pikiran akan faham yang menjadi pengetahuan mereka masing-masing sebagai gêgulang dalam seni lantunan kidung-kidung syair secara bergantian. Perbedaan itu dikarenakan slamêtan pada umumnya dilakukan tergantung pada keadaan dan kebutuhan, seperti orang yang selalu sakit-sakitan perlu ruwatan, serangan hama hebat di sawah kemudian diadakan mêtri desâ, minta hujan karena musimnya sudah terlambat lama, musim menggarap sawah sudah tiba maka diadakan labûh, ketika seorang wanita melahirkan maka diselenggarakan brôkôhan, dan lain sebagainya. Dasar liturgi selanjutnya adalah langkah teologis yang meliputi delapan dalil, yaitu: (1) Tulisan Suci yang dipandang memiliki otoritas nilai kebenaran sebagai Sabda Tuhan di dalam menyatakan kehendakNya atas manusia di tengah alam dan kehidupannya, (2) Kedaulatan Tuhan sepenuh88 nya atas kehidupan manusia dan ciptaan lainnya, (3) Kebiasaan para pengikut di awal kelompok kepercayaan sebagai norma praktis, (4) Penghayatan seluruh hari yang dijiwai oleh pengenangan akan karya penyelamatan Tuhan bagi manusia, (5) Pengajaran perintah Tuhan dan lambang-lambang tertentu yang disucikan secara khusus sebagai sakramen untuk acuan dan inti peribadahan, (6) Persekutuan sebagai salah satu wujud aneka peran dan karya berbeda tetapi satu kesatuan hidup bersama sebagai tubuh, yang menuntut (7) Peran serta seluruh anggota untuk saling melayani dalam keteraturan dan rasa hormat, (8) Norma Pastoral sehingga pelaksanaannya dapat mencapai tujuan sesuai dengan pergumulan keberadaan hidup yang khas dari umat. Walaupun ada perbedaan pijakan dan rupa penampilannya, tentu saja slamêtan juga memiliki unsur-unsur teologis beserta kegunaan yang intinya sama. Sama-sama bertolak dari nilai-nilai Illahi yang dinyatakan dalam sejarah kehidupan manusia, orang-orang Jawa meyakini pula adanya kedudukan kekuasaan sabda kehendak Hyang Kewâsâ secara mutlak atas kehidupan mereka. Hanya saja, ketentuan dalam wujud kanon seperti Alkitab tampaknya memang tidak ada pikiran membuat seperti itu. Ada banyak tulisan-tulisan khas pandangan Jawa yang keberadaannya sangat jelas dan terjaga hingga sekarang di tengah kalangan tertentu, khususnya kāratôn. Akan tetapi semuanya tidak memiliki alasan untuk menjadi acuan kebenaran sahih yang paling diutamakan. Semua memiliki kebenarannya masing-masing. Karena itu tulisan-tulisan tersebut diakui dan diterima 89 seluruhnya oleh masyarakat Jawa sebagai himpunan karwûh adi luhûng (pengetahuan kebenaran yang amat luhur dan tinggi). Kedudukannya bisa dianggap sejajar ataupun disesuaikan dengan nilai-nilai penerapan yang dijumpai oleh masyarakat setiap hari sebagai penghayatan. Bila dibandingkan dengan keadaan alam dan kekuasaan kepemimpinan masyarakat yang cenderung nyaman, maka watak batin dinamis dan harmoni yang didukung oleh daya kekuatan tata jalinan hubungan percakapan membuat orang-orang Jawa tidak mengalami kesulitan untuk menemukan kebenaran yang menjadi kehendak Hyang Kewâsâ; termasuk untuk belajar karwûh adi luhûng yang dapat mereka lakukan dengan nggêguru (berguru). Itulah sebabnya masih banyak orang Jawa yang suka pada gêgulang, pitutûr, bahkan percaya pula pada gugôn tuhôn yang turun-temurun dari para leluhur yang diwejangkan oleh para sesepuh dan kaum cendekia, dengan penerimaan seperti percaya pada raja atau pendeta yang mewakili Tuhan dalam falsafah: sabdâ pāndhitâ-ratu, tan kênâ wola-wali (perkataan raja adalah sabda Tuhan karena dia wakilNya, sehingga tidak patut diulangi, seakan ada kesalahan). Kemutlakkan tersebut sekaligus juga menjadi dasar salah satu sisi etika yang menekankan ketaatan penuh terhadap kekuasaan Sang Pencipta, tunduk pada segenap ketetapanNya dalam tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing orang dengan saling menjaga untuk keselarasan hidup. Hanya saja, barang-barang ataupun kegiatan tertentu yang disucikan secara khusus dan dibakukan sebagai lambang-lambang sarana peneguhan dan pemeliharaan keselamatan sebagai sakramen yang menjadi pusat 90 berliturgi juga tidak mungkin disamakan dalam slamêtan. Sebagaimana roti, anggur, serta air yang dipakai sebagai lambang-lambang sakramen yang menjadi inti liturgi pada umumnya telah diakui menjadi milik Kekristenan khas yang sesungguhnya berasal dari budaya tertentu, maka slamêtan juga memiliki wujud khas menurut budaya Jawa dengan tujuan seperti itu. Dalam ritual Jawa yang selalu dikenal adalah tumpêng lengkap dengan ìngkûng dan banyu tâwâ untuk diterima dan dimakan atau diminum bersama, maupun banyu kêmbang yang kegunaannya sering dipercikkan atau disiramkan untuk mandi. Semua itu sarat dengan makna penebusan, pensucian, pembersihan, peresmian, pengenangan, serta kebersamaan, menurut pemahaman yang akrab diterima dan dilaksanakan masyarakat Jawa sendiri. Jadi pada intinya, menurut pengertian etimologi, definisi, beserta dasar-dasar slamêtan, upacara kepercayaan Jawa itu sesungguhnya merupakan liturgi, bahkan liturgi yang kontekstual karena kekhasannya. Sebaliknya, sebuah liturgi pada hakikatnya merupakan ungkapan keyakinan yang kontekstual pula, karena pada proses kemunculan maupun perkembangannya tersusun oleh berbagai latar belakang kehidupan yang menjadi pengalaman dan pemahaman di dalam keyakinan atau bangunan teologi manusia beserta unsur-unsur budaya yang membentuknya. Dengan kata lain, slamêtan itu sendiri sebenarnya juga merupakan teologi kontekstual masyarakat Jawa. 91 2.5. Liturgi Kontekstual Jawa dan Teologi Kontekstual Jawa Uraian tata susunan upacara kepercayaan Jawa di atas pada intinya memiliki urut-urutan sebagai berikut: (1) Pemberian sesaji kepada Hyang Kewâsâ untuk memuji, mengucap syukur, ataupun tebusan atas kesalahan dari pihak manusia. (2) Penyampaian ujûb kepada khalayak. (3) Pemanjatan doa permohonan berkat bagi yang sedang menjalani slamêtan. (4) Pembagian bancaan untuk dinikmati bersama. Meskipun di dalam persiapannya cukup rumit karena banyaknya barang-barang kebutuhan yang harus disediakan sebagai syarat (ubârampe) sangat beragam, akan tetapi di dalam pelaksanaannya upacara itu sesungguhnya sederhana dan khas. Namun kekhasan slamêtan sebagai liturgi kontekstual Jawa tidak hanya sebatas tampilan-tampilan luar. Meminjam istilah Huang Po Ho dan Sedmak, berbagai tampilan luar liturgi Jawa itu merupakan cerminan keyakinan (teologi) maupun berkeyakinan (berteologi) yang bersifat kontekstual sebagai hal yang paling pokok. Seperti dinyatakan di dalam Bab I, teologi kontekstual adalah teologi yang mengambil konteks, situasi dan kondisi daerah tempat tinggal, sejarah dan kebudayaan umat di tengah masyarakat sebagai sumber refleksi dan pengakuan iman, serta untuk membangunan teologi yang dapat membentuk identitas relevan dengan konteksnya.138 Sedangkan berteologi kontekstual yang oleh Sedmak disebut juga berteologi lokal adalah teologi yang dihasilkan dari perhatian penuh pada suasana keadaan-keadaan khusus dalam kehidupan manusia di ling138 Huang Po Ho, No Longer a Stranger, 13. 92 kungan sekitar di bumi ini dan berhubungan penting dengan budaya tertentu di manapun, di sini dan saat ini yang meliputi politik, ekonomi, maupun spiritual.139 Karena itu kekhasan pokok dari liturgi upacara kepercayaan Jawa tadi adalah inti teologi ataupun berteologinya. Teologi khas yang menjadi sumber tata susunan upacara kepercayaan Jawa sudah cukup jelas diterangkan dalam bagian sebelumnya tentang faham dan berbagai wujudnya. Pada intinya orang Jawa mengimani bahwa Tuhan itu ada. Dia adalah Sang Pencipta Maha Kuasa dan Maha Suci yang memiliki hakikat transenden, dan sebagai sosok hakiki itu mampu berimanensi dalam rupa profan (Gûsti tan kênâ kinirâ-kirâ, aywâ tan kenâ kinâyâ ngâpâ, ngìng bisâ rinâsâ; Gûsti iku dumunûng ìng ngêndi papan, anéng sirâ ugâ ânâ Gûsti). Meminjam istilah M. Sastrapratedja, asas faham kebudayaan Jawa itu disebut juga sebagai teologi kodrati (teologi naturalis), yaitu teologi yang mengajarkan tentang Allah yang keberadaanNya dapat diketahui dengan akal budi manusiawi melalui barang-barang atau bendabenda ciptaan. Dalam hubungan DiriNya dengan manusia dan demikian pula sebaliknya, keberadaanNya tidak dibatasi oleh pewahyuan saja.140 Itulah mengapa liturgi kontekstual Jawa secara lahiriah nampak berkiblat pada alam, seperti laut, sungai, gunung, hutan, sawah maupun ladang, benda-benda yang dianggap bertuah atau memiliki kekuatan gaib, dan lain sebagainya. Sebab wahana itu memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari139 Clemens Sedmak, Doing Local Theology: A Guide for Artisans of a New Humanity (Maryknoll, New York: Orbis Books, 2006), 3-4. 140 M. Sastrapratedja, Allah Sebagai Dasar Ada: Filsafat dan Teologi Paul Tillich (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2001), 16. 93 hari orang Jawa. Bagi mereka, aneka rupa alam itu memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pencaharian kebutuhan pokok untuk hidup dan kehidupan. Bahkan rupa-rupa alam beserta dengan kekuatannya itu menjadi bernilai pula secara spiritual. Melalui alam dan kekuatannya orang-orang Jawa merasa yakin bisa menemukan atau berjumpa dengan Tuhan, Sumber kehidupan dan keselamatan dalam berbagai wujud kuasaNya sebagai pengalaman praktis dan nyata. Kekhasan liturgi kontekstual Jawa tersebut tidak terpisahkan dengan inti yang terdapat pada sisi berteologinya. Seperti disajikan secara ringkas pada bagian sebelumnya tentang wujud aneka jenis upacara kepercayaan Jawa maupun tata susunan dan isinya, berteologi sebagai tindakan pengungkapan keyakinan yang menggunakan cara tertentu dan rupa-rupa lambang dalam slamêtan juga khas. Lambang-lambang itu berupa piranti-piranti yang berasal dari alam untuk menggambarkan gagasan-gagasan tentangnya sebagai sarana untuk menghubungkan keberadaan Tuhan dan manusia, maupun etika kehidupan menyeluruh. Sekian banyak lambang yang dimungkinkan ada dalam berbagai slamêtan, tumpêng merupakan piranti wajib diadakan dan tak tergantikan. Sebab ubârampe itu adalah lambang pusat yang menggambarkan gunung dengan makna penyembahan Tuhan Maha Agung di tempat tinggi dan mulia (sêmbah Hyang), sekaligus cerminan alam dan etika kehidupan yang serasi dalam tanggung jawab politik tiap pribadi manusia untuk mengatur di tengah kedudukan kemasyarakatannya, seperti makna yang terdapat pada pokok pengertian jagad gêdhe dan jagad cilìk. Inilah acuan aksi dan refleksi orang 94 Jawa dalam berbagai kehidupan berkebudayaan yang sampai sekarang tetap ada walaupun pada keadaan tertentu seakan tersamar oleh berbagai macam perubahan jaman di tengah masyarakatnya. 2.6. Penutup Dari semua sudut kajian liturgi dan kontekstualisasinya di tengah budaya dan sejarah Kekristenan, khususnya di dalam budaya kehidupan masyarakat Jawa dengan pandangan beserta tradisi ritual keagamaannya di atas, maka liturgi kontekstual dalam budaya Jawa disimpulkan sebagai tata perilaku keagamaan masyarakat Jawa untuk pengungkapan keyakinan akan pengalaman tentang karya penyelamatan Tuhan di seluruh segi kehidupan yang terbingkai dalam teologi Kêjawén dan terpusat pada lambang tumpêng maupun berbagai kelengkapan terkait untuk mengkomunikasikannya. Liturgi kontekstual Jawa tersebut memberikan peringatan akan karya pertolongan Tuhan, sekaligus mendorong setiap orang untuk ikut serta menikmati anugerahNya itu, dan mau terlibat aktif menjaga keselamatan dengan tindakan menurut kedudukan dan peran yang telah ditetapkan (pêpêsthi). Pelaksanaan liturgi adat kepercayaan Jawa itu bertujuan untuk menciptakan keselamatan atau kehidupan harmoni semua orang beserta alam yang menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan berpijak dari Kekristenan, liturgi kontekstual dalam budaya Jawa dapat disimpulkan sebagai liturgi yang dibangun dengan melibatkan atau mendayagunakan pandangan maupun tradisi kepercayaan beserta aneka lambang yang berasal dari budaya 95 masyarakat Jawa di tengah suasana keberadaan hidup mereka sebagai langkah penyesuaian untuk menyampaikan gagasan Injil Kristus secara efektif, yaitu penyataan Tuhan yang menyelamatkan manusia sebagai kasih karunia yang terjelma di dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi manusia, dan dilambangkan dengan sakramen. Jadi, liturgi kontekstual dalam budaya Jawa tidak cukup hanya ditentukan oleh penggunaan bahasa Jawa atapun pakaian tradisionalnya, tetapi dengan keseluruhan tata kehidupan masyarakat Jawa, sehingga Injil Kristus dapat dijumpai dan dialami di dalam segi-segi kebudayaan Jawa beserta suasana dan keberadaan yang tengah terjadi sebagai konteks yang saling mempengaruhi.141 141 F. J. Clasen, “Liturgy on the Edge of Change”. Practical Theology in South Africa 2010. 23, no. 1 (2010), 36-54. 96