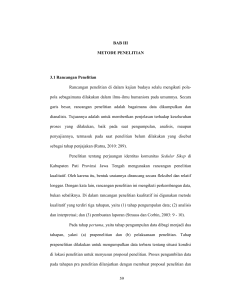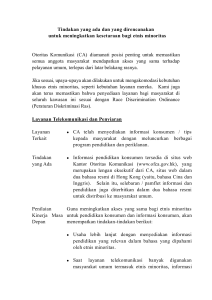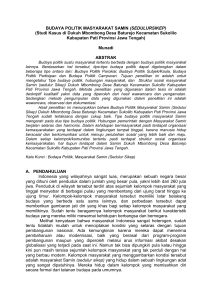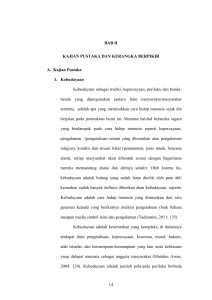Kelompok Minoritas dan Strategi Non
advertisement

Kelompok Minoritas dan Strategi Non-Konfrontasi Refleksi Lapangan di Komunitas Sedulur Sikep dan Parmalim Oleh Uzair Fauzan Sejak reformasi, perubahan telah banyak terjadi di jagad politik Indonesia. Krisis ekonomi yang berujung pada pendongkelan kekuasaan Soeharto telah menggerogoti banyak sendi kekuatan negara. Negara yang dulu pernah sangat adidaya, yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai power-house state, sekarang harus menerima suratan takdir bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya kekuatan yang bermain dominan di ranah publik. Di tengah kebangkrutan negara itu, masyarakat sipil memperkuat barisannya dan memperkenalkan banyak perubahan ke dalam sistem politik. Dengan banyak panduan dari transitologi, atau ilmu tentang transisi menuju demokrasi, perubahanperubahan itu banyak diarahkan pada pembenahan dalam politik pemilihan (electoral politics) dan penguatan institusi-institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, juga perlu disebut berdirinya lembaga-lembaga negara baru yang diyakini akan memperkuat transisi menuju demokrasi dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara, seperti Mahkamah Konstitusi. Muncul keyakinan bahwa penguatan institusi-institusi tersebut diperlukan untuk menjamin keberadaan saluran yang bisa digunakan oleh warga negara untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka. Dalam perjalanannya, berbagai komunitas warga negara memang terbukti menggunakan jalur-jalur tersebut untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan terbukanya saluran-saluran demokrasi itu, pilihan bergerak semakin beragam. Bila warga tidak puas dengan keputusan pemerintah, militer atau kelompok pemodal, terbuka kesempatan luas untuk menggugatnya dengan model citizen law suit, pengadilan tata usaha negara, atau judicial review. Bagi orang awam, keberadaan saluran hukum yang berjalan relative sangat transparan itu membuat warga negara semakin memiliki keberanian untuk menentang secara langsung pemerintah atau kelompok pemodal yang merugikan hak-hak mereka. Sekarang, kita bisa menemukan berbagai kasus dimana orang-orang awam, yang sebelumnya hampir tidak memiliki kepercayaan di depan hukum dan tidak memiliki pengalaman berurusan dengan hukum secara langsung, tiba-tiba bangkit melawan kesewenang-wenangan di pengadilan. Kasus paralegal kaum miskin kota, ibu-ibu rumah tangga yang membela anak-anaknya yang tidak lolos UAN hanyalah beberapa contoh yang bisa disebut untuk menggambarkan perubahan itu. Tapi, apakah inklusivisme system hukum yang sekarang muncul itu sudah dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat? Bagaimana dengan kelompok minoritas yang sekian lama dipinggirkan oleh kebijakan negara yang enggan memberi status kewarganegaraan penuh kepada mereka? Apakah mereka juga mengambil langkah yang sama dengan berhadapan langsung dengan negara untuk menuntutnya berubah? Jika tidak, factor apakah yang menyebabkan mereka enggan melakukannya? Apakah karena mereka tidak well-informed tentang perubahan kontemporer dalam system hukum di negara ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang hendak saya bahas dalam tulisan singkat ini. Tulisan ini adalah hasil refleksi saya setelah bergaul dengan komunitas sedulur sikep di daerah Pati (Jateng) dan komunitas parmalim di Medan. Komunitas Sedulur Sikep Pati Salah satu komunitas sedulur sikep di Pati bermukim di dusun Bombong-Bacem, desa Baturejo, kec. Sukolilo. Menurut laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Pati pada Juli 2003, sedulur sikep yang mendiami dusun Bombong-Bacem berjumlah 123 KK dan 633 jiwa. Namun, menurut pemetaan yang dilakukan sedulur sikep sendiri, per Desember 2004 ada 148 KK dan 706 jiwa. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk desa Baturejo yang berjumlah 5752 orang, total jumlah sedulur sikep di desa ini berkisar 10 persennya (Uzair Fauzan, Politik Representasi dan Wacana Multikulturalisme dalam buku Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Interseksi, 2005). Meski kebanyakan tidak mengenyam pendidikan sekolah formal, tak sedikit warga Sikep yang memiliki kemampuan baca-tulis (pergi sekolah formal sendiri merupakan pantangan yang dipegang teguh oleh komunitas ini). Kemampuan baca tulis ini biasanya diperoleh dari orang tua langsung atau mengikuti pendidikan informal yang digagas oleh warga Sikep sendiri. Dengan kemampuan ini, mereka tidak kesulitan memperoleh informasi dari media cetak atau televisi. Akses terhadap informasi semakin mudah karena pergaulan (srawung) luas yang mereka miliki dengan komunitas luar (sedulur liyo totocoro). Keberadaan Kang Gunritno sebagai figur yang punya banyak relasi di luar komunitas sangat membantu komunitas ini mencerna perubahan. Relasi dan jaringan yang dia miliki sangat beragam, mulai dari birokrat dan politisi lokal Pati, seniman seperti Emha atau Slamet Gundono, akademisi dan aktivis/pekerja sosial nasional, hingga gubernur Mardiyanto. Meski dia sendiri aktif mengambil bagian dalam berbagai ikhtiar pemecahan berbagai persoalan politik, sosial dan ekonomi petani, termasuk di antaranya menjadi “pejabat” Serikat Petani Pati (SPP) yang sangat aktif melakukan program-program pemberdayaan, namun hampir bisa dipastikan bahwa dia dan sedulur sikep lain yang aktif di Serikat yang sama tidak akan pernah tampil di depan publik menghujat pemerintah secara terbuka laiknya para aktivis sosial dan demonstran. Kalaupun harus menyuarakan kritik dan berhadapan dengan pemerintah, wajah Kang Gun jarang sekali menampakkan pengencangan otot-otot lehernya. Alih-alih tegang, ia sampaikan kritiknya secara tenang dan acapkali dibumbui dengan sanepo (perumpamaan/metafora) yang kaya. Di tingkat internal komunitas, strategi yang cenderung mengutamakan harmoni itu juga acapkali bisa kita temukan, terutama jika menyangkut kesalahpahaman antara kelompok muda dan kelompok tua. Kaum muda disini dimotori oleh Kang Gunritno, sedangkan kaum tua dipersonifikasikan oleh sosok Mbah Tarno. Seperti yang sudah disebut, kaum muda dibawah kepemimpinan Kang Gunritno punya pergaulan luas dengan berbagai kalangan, sedangkan kaum tua lebih banyak tinggal di kampung, mengurusi persoalan keluarga batih, dan ladang pertanian mereka sendiri. Karena pergaulannya yang luas, kaum muda lebih menyerap banyak informasi yang kemudian menjadi dasar bersikap yang ujungnya bisa sangat berbeda dengan sikap kelompok tua. Kaum tua sendiri tak jarang memandang miring aktivisme sedulur sikep yang dibangun oleh Kang Gunritno. “Wong sikep kok ngono” adalahujaran kaum tua yang sering diucapkan untuk mengomentari aktivisme itu. Untuk menjembatani perbedaan sikap di antara kedua kelompok ini, biasanya ada sekelompok warga yang akan berperan sebagai penyeimbang yang sering disebut oleh kalangan sedulur sikep di Bombong-Bacem sebagai penamping. Penamping inilah yang berperan sebagai messenger ulang-alik di antara keduanya. Dalam banyak hal, peran yang dimainkan olehpenamping ini berperan besar menjaga iklim persaudaraan di komunitas ini. Komunitas Parmalim di Medan Kelompok Parmalim yang disebut di sini adalah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Punguan Parmalim Bale Partonggoan Huta Tinggi Laguboti. Seperti namanya, komunitas ini berpusat di Huta Tinggi, Laguboti, Kab. Toba Samosir. Meski ada beragam versi yang mengatakan bahwa komunitas ini melakukan percampuran adat Batak dengan ajaran-ajaran agama besar, namun komunitas ini sendiri meyakini bahwa ajaran mereka berasal dari Si Singamangaraja XII yang kemudian diteruskan oleh Raja Mulia Naipospos. Sekarang ini, jumlah keluarga Parmalim diperkirakan tak kurang dari 5000 KK yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kelompok jemaat atau cabang mereka juga mulai berkembang. Jika pada tahun 1994, ada sekitar 30punguan yang resmi diakui oleh Huta Tinggi dan 4 punguan lainnya masih belum diresmikan, angka itu mengalami peningkatan pada tahun 2000. Di tahun ini sudah ada 36 punguan di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Batam, Palembang dan terutama tersebar di berbagai kota lainnya di Sumatera Utara. Angka penyebaran yang meningkat ini erat terkait dengan semangat manombang, yaitu semangat merantau untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang juga tertanam dalam komunitas ini. Manombang ini sendiri ditopang oleh pandangan hidup komunitas yang mendorong penerimaan terhadap perkembangan jaman yang baru, asalkan tidak mengorban nilainilai spiritual Batak. Menurut Monang Naipospos, ada tiga nilai yang disebutnya sebagai “motto” yang memandu orangorang Parmalim dalam berhadapan dengan perkembangan jaman (modernitas). Ketiganya adalah parbinotoan naimbaru(menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia),marngolu naimbaru (menerima perkembangan jaman untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban tanpa melanggar etika sosial sesuai tuntutan ajaran Ugamo Malim), dan tondi na marsihohot (tetap bertaqwa kepada Tuhan Debata Mulajadi Nabolon melalui ajaran Sisingamangaradja-Raja Nasiakbagi tanpa dipengaruhi ajaran keyakinan agama lain). Dengan pandangan hidup ini, tak heran jika kita menemukan banyak warga Parmalim yang mengenyam pendidikan modern hingga perguruan tinggi dan bekerja di berbagai perusahaan terkenal, seperti Standard Chartered Bank atau Freeport. Walhasil, dunia luar yang dibentang dan terbentang luas itu (kecuali di sektor kepegawaian pemerintah) bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi warga komunitas minoritas ini. Sedikit berbeda dengan komunitas Sikep, hampir tidak ada perbedaan antara kaum muda dan kaum tua menyangkut respons terhadap modernitas (termasuk institusi-institusi modern seperti sekolah). Kendati begitu, bila muncul persoalan dengan komunitas luar, respons mereka cenderung serupa. Seperti yang terjadi dalam kasus sengketa pembangunan bale parsaktian di daerah Air Bersih Ujung kelurahan Binjai, Medan. Alih-alih menyelesaikannya di depan hukum, komunitas Parmalim Medan selalu memilih untuk memaksimalkan lobi dan pendekatan dengan berbagai kelompok yang menentang pembangunan itu. Bertolak belakang dengan kelompok penentangnya yang selalu mengandalkan (imaji) kekuatan massa, komunitas Parmalim memanfaatkan jalur-jalur personal dan informal. Jalur-jalur personal-informal itu tidak hanya ditujukan pada actor-aktor partikelir seperti pendeta HKBP Air Bersih, HKBP Pusat dan berbagai organisasi gereja yang berkaitan dengan HKBP; tetapi juga kepada representasi negara seperti Lurah Binjai atau Dinas Tata Kota. Katanya, mereka bahkan dengan tegas menolak usulan kolega mereka untuk melakukan gugatan hukum kepada negara. Refleksi Dalam kajian gerakan sosial, biasa dikenal adanya struktur kesempatan politik yang memungkinkan atau tidak memungkinkan aktor sosial untuk bergerak. Struktur kesempatan politik (political opportunity structure) itu didefinisikan oleh Sidney Tarrow sebagai “consistent—but not necessarily formal, permanent, or national—signals to social or political actors which either encourage or discourage them to use their internal resources to form social movements” (dalam Keck and Sikkink, Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Press, 1998). Struktur kesempatan politik itu dikenal terbagi dua, yaitu yang bersifat statis dalam pengertian berkait dengan kelembagaan negara (bersifat eksternal terhadap aktor gerakan) seperti terbukanya system politik, transparansi pengadilan; dan struktur kesempatan politik yang bersifat dinamis, yang erat terkait dengan kondisi internal di dalam aktor-aktor gerakan (masyarakat sipil) itu sendiri, seperti lemah/kuatnya solidaritas, aliansi, dan sejenisnya. Gerakan sosial yang berhasil biasanya memiliki dua bentuk struktur kesempatan itu. Bila ditempatkan dalam bingkai analisis ini, perubahan sistem politik yang terjadi pascareformasi sebenarnya baru menyumbang salah satu syarat keberhasilan gerakan sosial. Bila ingin benar-benar berhasil, gerakan sosial juga harus ditunjang oleh syarat lainnya, yaitu kekompakan internal di dalam masyarakat sipil itu sendiri. Syarat kedua ini sendiri masih harus ditunggu hasil akhirnya. Sekilas, hasil sementara menunjukkan kecenderungan yang semakin memburuk. Memburuknya situasi masyarakat sipil, yang antara lain bisa dilihat dari meningkatnya premanisme dan menguatnya gelombang fundamentalisme, tentu saja menciptakan ancaman tersendiri bagi mereka yang ingin memperjuangkan haknya, terutama kelompok minoritas. Dengan status minoritasnya yang rentan (entah karena jumlah warga yang minimal maupun identitas yang rentan dipukul karena trauma [politik] masa lalu), kelompok seperti sedulur sikep dan parmalim tampaknya secara strategis sengaja memilih strategi nonkonfrontasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Latar belakang sosial dan pandangan hidup dua komunitas ini, dua faktor minimal yang diurai di tulisan singkat ini, menunjukkan secara jelas bahwa keduanya mengambil strategi non-konfrontatif BUKAN KARENA mereka tidak punya sumberdaya untuk melakukan strategi konfrontatif. Dengan akses mereka yang terbuka pada informasi, sulit dibantah jika mereka tahu betul soal perkembangan mutakhir sistem politik atau sistem hukum di negeri ini. Strategi non-konfrontatif mereka bisa jadi diambil karena dua hal (1) pandangan hidup mereka yang mementingkan harmoni; atau (2) mereka tidak yakin bahwa masyarakat sipil yang menjadi rekan kerja mereka belum cukup kuat untuk menanggung resiko yang mungkin muncul jika mereka melakukan strategi konfrontasi. Strategi konfrontatif bisa jadi menempatkan keselamatan komunitas sebagai taruhannya, harga yang bisa jadi dianggap terlalu mahal untuk dibayar oleh komunitas ini. Bila asumsi ini benar adanya, barangkali harus dilakukan pembagian peran dalam gerakan untuk memperjuangkan status kewarganegaraan yang sejajar bagi komunitas minoritas. NGOs dan kelompok masyarakat sipil non-komunitas minoritas bisa mengambil peran lebih besar pada konfrontasi terbuka di depan hukum, seperti uji materi terhadap produk perundangan yang membatasi pengakuan resmi hanya pada 6 agama saja; pada saat yang sama, komunitas minoritas lebih banyak berperan dalam penguatan jaring-jaring informal dengan berbagai komunitas mayoritas lain yang berpotensi menjadi kawan sekaligus lawan, seperti pondok pesantren atau gereja. Dalam konteks ini, strategi kultural menjadi sama pentingnya dengan strategi reformasi hukum. Penulis adalah koordinator Perkumpulan Lafadl, Yogyakarta