Dukacita dan Kehilangan pada Orang Toraja dalam Ritual Ma`nenek
advertisement

BAB II KAJIAN PUSTAKA Dukacita dan kehilangan adalah respon emosional yang dialami manusia pada umumnya akibat kematian orang-orang yang dikasihinya. Kematian adalah fakta universal yang dialami oleh manusia di seluruh dunia, dan ketika menghadapi kenyataan tersebut manusia juga tidak dapat memisahkan diri dari kebudayaan di mana terdapat cara-cara yang unik untuk berkabung sesuai dengan adat dan ritual masing-masing. Istilah dukacita dan kehilangan telah banyak digunakan oleh para ahli yang melakukan penelitian indigenous pada suatu masyarakat tertentu dengan keunikan budayanya masing-masing. Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi umum mengenai beberapa konsep yang menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan yaitu pengertian dukacita dan kehilangan, sifat utama duka cita, faktor-faktor yang mempengaruhi dukacita, gejala-gejala utama proses dukacita, tugas proses berduka, kompleksitas kedukaan, ritual Ma’nenek serta aspek-aspeknya. A. Dukacita dan Kehilangan 1. Pengertian dukacita dan kehilangan Dukacita (grief) adalah sebuah sistem perasaan, pikiran dan perilaku yang dipicu ketika seseorang diperhadapkan pada peristiwa kehilangan, yaitu kematian orang yang dikasihi (Jeffreys, 2005). Dukacita adalah sebuah respons yang muncul ketika seseorang merasa kehilangan. Attig (dalam Leming & Dickinson, 2006) mengatakan bahwa dukacita adalah kekuatan emosi yang sangat besar yang sering dipicu oleh kematian, terlebih khusus kematian orang yang dicintai. 12 Dukacita adalah emosi atau perasaan kehilangan yang dapat dialami oleh semua orang saat kematian orang yang dicintai ataupun orang yang dekat, misalnya keluarga, kekasih, atau sahabat; bahkan dapat juga saat kehilangan barang yang dianggapnya sangat berharga (Helmer, 1975). Dalam Wiryasaputra (2003) Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata Grief (kedukaan) didefenisikan sebagai penderitaan batin yang sangat dalam akibat suatu peristiwa kehilangan. Sementara menurut Sterling (2003), dukacita adalah respon terdalam setiap individu terhadap peristiwa kehilangan. Dukacita merupakan sebuah pengalaman universal dalam diri manusia yang kompleks dan menimbulkan perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masyarakatnya. Dukacita mengacu pada emosi yang subjektif dan afek yang merupakan respon normal terhadap kehilangan (Gibson, 2007). Seseorang yang berduka tidak hanya melibatkan isi yakni apa yang dipikirkan, dikatakan dan dirasakan individu tetapi juga proses bagaimana individu berpikir, berkata dan merasa. Dukacita merupakan kesedihan mendalam dan berkepanjangan yang selalu berkaitan langsung dengan kehilangan seseorang yang dianggap penting, sangat berarti dan bernilai (Hillers, 1992). Dengan demikian dukacita adalah respon yang normal terhadap kehilangan hubungan personal, status, tujuan, harga diri dan berbagai hal penting lainnya. Dukacita merupakan reaksi pertahanan diri dan tanggapan seseorang secara holistik atas peristiwa kehilangan yang sedang dirasakannya, sebuah reaksi normal terhadap suatu peristiwa kehilangan atas sesuatu yang berharga. Kehilangan didefenisikan sebagai respon dukacita karena berpisah dari seseorang yang sangat berarti, rasa sedih yang berkepanjangan sebagai ekspresi dukacita bukan hanya oleh kematian tetapi juga kehilangan makna 13 secara mendalam karena ditinggal orang yang dikasihi (Max, 1997). Menurut Scheineider (1984) kehilangan terkait erat dengan kenangan. Rasa kehilangan merupakan suatu fenomena yang tidak mungkin dapat dipahami secara langsung karena sifatnya unik, ekspresinya sangat tergantung pada budaya dan struktur perasaannya tak terlukiskan. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa individu membangun hubungan dengan diri sendiri dan orang lain melalui kehilangan: kehilangan orang yang dicintai, kehilangan diri sendiri dan kehilangan masa lalu. Di sini kepribadian, subyektivitas dan individualitas, proses di mana melaluinya individu sampai pada mengenali/mengakui dirinya terpisah dan berbeda dari orang lain, dibentuk di dalam dan melalui pengalaman kehilangan yang menyakitkan. Orang yang mengalami rasa kehilangan sering kali ambivalen; tidak bisa menangis, berkabung, perasaan negatif, rasa marah, penyangkalan dan rasa bersalah sebagai sebuah aspek kesedihan alami sampai ia benar-benar pulih. Reaksi kesedihan sangat lama sehingga individu terlibat dalam berbagai cara sebagai bentuk penyangkalan guna melindungi diri dari rasa kehilangan yang melandanya. Persepsi dan reaksi atas kehilangan sangat unik dan sifatnya individual (Sterling, 2003). Marrone (1997, p.23) mengatakan “You can’t have grief without loss”. Dukacita dan kehilangan adalah ekspresi perasaan mendalam yang tak terpisahkan karena setiap kehilangan pasti menyebabkan dukacita (grief). Itulah sebabnya setiap orang takut menghadapi kematian (Adam, 1999). Hal tersebut nampak juga dari pandangan Cowles dan Rodgers (1991), yang menggambarkan duka cita sebagai kesedihan panjang dan mendalam disebabkan oleh kehilangan seseorang yang dicintainya (misal kematian): 1. Duka cita dilihat sebagai suatu keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah. Duka cita tidak berbanding lurus dengan keadaan emosi, pikiran maupun perilaku seseorang. Duka cita adalah suatu 14 proses yang ditandai dengan beberapa tahapan atau bagian dari aktivitas untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : (1) menolak (denial); (2) marah (anger); (3) tawar-menawar (bargaining); (4) depresi (depression); dan (5) menerima (acceptance).Pekerjaan duka cita terdiri dari berbagai tugas yang dihubungkan dengan situasi ketika seseorang melewati dampak dan efek dari perasaan kehilangan yang telah dialaminya. Duka cita berpotensi untuk berlangsung tanpa batas waktu. 2. Pengalaman duka cita dan kehilangan bersifat individu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Duka cita lebih dari sekedar tetesan air mata, dimana ia memanifestasikan dirinya sendiri dalam kesadaran, fisik, tingkah laku, jiwa, psikologis, dan kehidupan sosial seseorang, seperti halnya perilaku emosional. 3. Duka cita bersifat normatif namun tidak ada kesepakatan universal yang bisa menjelaskan sejauh mana kondisi normalnya. Berdasarkan defenisi dan uraian tentang dukacita dan kehilangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dukacita dan kehilangan adalah ekspresi perasaan mendalam yang menyertai peristiwa kematian orang-orang terdekat yang sangat berarti. Dukacita dan kehilangan merupakan reaksi emosi setiap individu merespon kematian orang yang dikasihinya. Pengalaman kehilangan dan dukacita adalah hal yang esensial dan normal dalam kehidupan manusia. Membiarkan pergi, melepaskan dan terus melangkah menjalani kehidupan ini, hanya dapat dilakukan oleh individu yang dapat mengekspresikan perasaan kehilangan yang dialaminya. 15 B. Sifat utama dukacita 1.Dukacita bersifat unik Dukacita dapat terjadi pada orang yang sama, mengalami peristiwa kehilangan yang sama namun kedalaman dukacitanya berbeda. Perbedaan kedalaman itu dapat disebabkan oleh waktu, kondisi dan situasi yang berbeda. Tidak ada kedukaan yang sama sebab proses dukacita bukanlah merupakan sebuah proses garis lurus, melainkan seperti seutas tali yang melingkar-lingkar (Wiryasaputra, 2003). 2.Dukacita bersifat holistik Selain bersifat unik, khas, personal, situasional dan kontekstual dukacita juga merupakan pengalaman yang bersifat holistik. Dalam pandangan holistik ada empat aspek utama kehidupan yang dipandang sebagai satu kesatuan utuh secara sinergistik, yakni: fisik, mental, spiritual dan sosial. Kubler-Ross (1969) menjelaskan bahwa aspek fisik berkaitan dengan tubuh manusia yang dapat dilihat dan diraba atau disentuh. Inilah aspek somatis yang juga berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebersihan tubuh, lingkungan alam dan metabolisme tubuh. Sementara aspek mental berhubungan dengan cara manusia dapat menghidupkan, memberadakan dan membedakan dirinya. Dalam aspek ini manusia menjadi pribadi yang otonom dan memiliki identitas diri. Aspek mental berhubungan dengan pikiran, emosi (pikiran positif dan negativ), motivasi, harga diri, integritas dan kreatifitas diri. Sedangkan aspek spiritual memungkinkan manusia memiliki visi, misi dan harapan yang jelas dalam hidup. Aspek tersebut memungkinkan manusia tetap memberadakan dirinya sebagai manusia dengan nilai-nilai leluhurnya. Yang terakhir adalah aspek 16 sosial yakni aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok bermasyarakat. Dalam hubungan dengan dukacita melalui keempat aspek inilah manusia dikatakan manusia yang sinergik yaitu manusia yang mampu bertumbuh melalui pengalaman kehilangan atas kematian. Artinya manusia tidak mampu menghindar dari pengalaman dukanya, melainkan harus masuk dan merangkul pengalaman dengan jiwa yang terbuka. Adapun gejala-gejala dukacita secara holistik berdasarkan keempat aspek tersebut, menurut Wiryasaputra (2003) adalah sebagai berikut: a.Aspek fisik Secara fisik umumnya muncul gejala-gejala seperti menangis, mata menerawang, mati rasa, kesemutan, tubuh gemetaran, kalau berjalan seperti melayang, tidak tenang, tubuh lemah, tenggorokan terasa kering, dada sesak, kejang-kejang, nasfas pendek, pusing, kadang terasa gatal-gatal, bisulan, perut nyeri atau mulas, diare, ingin kencing terus, perut kembung, tidak dapat tidur dengan pulas, ngilu di persendian, nafsu makan menurun atau bertambah dan nafsu sex juga menurun. b. Aspek mental Biasanya muncul gejala-gejala seperti tidak dapat menerima kenyataan (menyangkal, menolak) terkejut, sedih, bingung, gelisah, pikiran kacau tidak teratur, kehilangan konsentrasi, selalu berpikir dan merindukan yang hilang, mudah tersinggung, benci, marah, kecewa, putus asa, batin tertekan, perasaan menyesal yang berlebihan, rasa bersalah, merasa berdosa, merasa tidak berarti lagi, merasa sendiri atau kesepian dan kadang muncul keinginan untuk bunuh diri. 17 c. Aspek spiritual Dalam aspek ini gejala yang nampak adalah gejala seperti rasa berdosa, mempersalahkan Tuhan, marah pada Tuhan, tidak dapat konsentrasi misalnya saat berdoa, membaca kitab suci, tidak berminat mengikuti kegiatan keagamaan, merasa dikucilkan oleh kelompok keagamaannya, tawar menawar dengan Tuhan. d. Aspek sosial Gejala dukacita yang nampak melalui aspek ini, antara lain suka menyendiri, menarik diri, mengurung diri, selalu ingin menceritakan tentang sesuatu atau seseorang yang hilang secara berlebihan, suka mengunjungi makam atau tempat-tempat yang berhubungan dengan orang atau sesuatu yang hilang, mempersalahkan, marah bahkan membenci orang lain, bersikap kasar atau berlebihan dalam berbagai hal. Peristiwa kehilangan juga sering menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga. C. Proses dukacita dan aspek-aspeknya Menurut Bowlby (1980) proses berduka akibat kehilangan memiliki empat fase yaitu: 1. Mati rasa dan penyangkalan terhadap kehilangan 2. Tangisan dan kerinduan akibat kehilangan orang yang dicintai dan memprotes kehilangan yang tetap ada 3. Kekacauan kognitif dan keputusasaan emosional, mendapatkan dirinya sulit melakukan fungsi dalam kehidupan sehari-hari 4. Reorganisasi dan reintegrasi mengembalikan hidupnya 18 kesadaran diri sehingga dapat Pandangan tersebut menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Kubler-Ross (1969) tentang bagaimana kehilangan mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu ia mendeskripsikan aspek dan tahap dukacita sebagai suatu proses yang terdiri dari: a.Tangisan dan kerinduan. Kubler-Ross (1969) menyatakan bahwa tangisan sebagai bentuk ketidak berdayaan seseorang dalam menanggung rasa yang terpendam dalam hatinya. Dengan demikian menurutnya kematian hanya sekedar pemicu meluapnya emosi kepermukaan dan lalu menyentuh rasa yang bersemayam dalam hati manusia pada tahapan mencapai puncaknya maka secara otomatis seseorang akan meluapkan emosi atau perasaannya yang tak sanggup lagi menjadi bebannya, dalam bentuk tangisan. Contohnya “Sejak kepergiannya serasa air mata ini tidak cukup mengiringinya. Hanya linangan air mata yang setiap hari menghiasi harihariku karena duka yang mendalam ini”. Dari pernyataam ini terlihat jelas pandangan Kubler-Ross bahwa menangis dalam kaitannya dengan kedukaan adalah gejala yang normal dalam proses berduka dan merupakan tindakan manusiawi dalam menghadapi kedukaan. Dengan menangis si penduka menumpahkan isi hatinya, kepedihan batinnya dan semua yang menjadi bebannya diungkapkan. Menangis dalam proses berduka merupakan ekspresi dari kepedihan hati yang paling dalam. 19 b. Penolakan. Kubler-Ross (1969) mengartikan penolakan terhadap kematian sebagai sarana untuk mempertahankan diri secara psikologis dimana seseorang yang mengalami atau merasakan kematian orang terdekatnya berespons untuk tidak mau menerima atau mengakui keadaan sebenarnya yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami kehilangan belum atau tidak mau mengakui atau menerima keadaan yang sebenarnya. Penolakan merupakan suatu sarana untuk mempertahankan diri secara psikologis. Sebagai contok ekspresi penolakan dalam kedukaan dapat dilihat dari pernyataan, “dia tidak mungkin meninggal, ini hanyalah sebuah mimpi buruk”. Dari pernyataan ini menunjukan bahwa seorang yang mengalami kehilangan belum atau tidak mau mengakui atau menerima keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana Kubler-Ross (1969) dalam pandangannya berkaitan juga dengan penolakan, dapat dikatakan bahwa penolakan merupakan suatu sarana untuk mempertahankan diri secara psikologis. c. Kemarahan. Kubler-Ross (1969) mengartikan kemarahan sebagai suatu emosi primer, alami, dan matang yang dialami oleh semua manusia pada suatu waktu tertentu, dan merupakan sesuatu yang memiliki nilai fungsional untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian terhadap kematian, perasaan tersebut muncul sebagai reaksi atas kehilangan. Pandangan ini dapat dilihat dari pernyataan kedukaan yang diekspresikan lewat salah satu contoh pernyataan wawancara 20 Contohnya, “Tuhan tidak adil, mengapa anakku yang masih sangat muda harus menjadi korban kecelakaan itu”. Perasaan itu muncul sebagai reaksi kehilangan. Kemarahan tersebut dapat ditujukan pada orang lain (eksternal) dan dapat juga terhadap diri sendiri (internal). d. Putus asa. Kubler-Ross (1969) menyatakan bahwa putus asa sebagai kondisi kejiwaan yang mana seseorang merasa dan menganggap bahwa apa yang diinginkan tidak akan tercapai atau kondisi batiniah yang menganggap adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang dialaminya. Temuan di lapangan yang menunjukan respons putus asa sebagai mana yang disampaikan oleh Kubler-Ross (1969), terlihat tewat pernyataan Contohnya, “Tak ada artinya saya hidup lagi karena suami yang selama ini menjadi tumpuan harapan kami telah pergi”. Dalam keputusasaan seseorang sama sekali tidak memiliki harapan. Baginya hidup di masa kini dan masa depan adalah sesuatu yang gelap gulita. Gejala putus asa ini akan semakin dalam bila penduka tidak dapat menemukan teman atau orang lain yang bersedia mendampinginya pada masa-masa sulit. Perasaan putus asa akan semakin membuat tidak berdaya biasanya setelah upacara pemakaman. Semua anggota keluarga dekat, kenalan dan tetangga sudah kembali ke tempat masing-masing. Padahal pada saat itulah orang yang berduka sungguh-sungguh memerlukan orang yang mendampinginya. 21 e. Rasa bersalah. Kubler-Ross (1969) dalam tulisannya menyatakan bahwa Guilty feeling/ perasaan bersalah adalah suatu kondisi emosional yang dihasilkan dari pemahaman seseorang bahwa telah terjadinya perbuatan dan tindakan penyimpangan standar moral. Lebih lanjut Kubler-Ross (1969) menyatakan bahwa para ahli sepakat bahwa rasa bersalah ini bersumber dari kepedulian yang tinggi individu terhadap standar moral yang berlaku bagi dirinya atau berlaku dalam masyarakatnya. Temuan di lapangan yang menunjukan respons rasa bersalah sebagai mana yang disampaikan oleh Kubler-Ross (1969), tergambar dari pernyataan Contohnya, “saya merasa bersalah karena tidak dapat melakukan sesuatu untuk memperpanjang nyawa mama saya. Setelah menyadari adanya kehilangan biasanya si penduka berbalik pada diri sendiri. Menganggap dirinyalah yang paling bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah terjadi. f. Stres. Kubler-Ross (1969) menyatakan bahwa, seseorang mengalami beban yang berat tetapi orang tersebut tidak dapat mengatasi beban itu, maka tubuh akan berespon dengan tidak mampu terhadap beban tersebut, sehingga orang tersebut dapat mengalami stress. Respons atau tindakan ini termasuk respons fisiologis dan psikologis. Temuan di lapangan yang menunjukan respons stres sebagai mana yang disampaikan oleh Kubler-Ross (1969), ditemukan lewat salah satu pernyataan dari informan yang menyatakan, 22 Contohnya, “sejak dia pergi kepalaku tak berhenti sakit, maag juga tidak sembuh-sembuh sekalipun sudah ditangani dokter”. Dari pernyatan ini jelaslah konsep stres dalam kedukaan menurut Kubler-Ross yakni, stres merupakan reaksi terhadap bahaya atau ancaman yang ada. Dalam situasi tersebut sistem syaraf dan tubuh secara otomatis memobilisasi energi untuk mengahadapi bahaya tersebut. Tidak jarang peristiwa kehilangan akibat dukacita menimbulkan gejala-gejala fisik seperti mati rasa, tubuh tidak berdaya, badan gemetaran, gangguan pencernaan, gatal-gatal, pegal-pegal dan sebagainya. g. Depresi. Menurut Kubler-Ross (1969), depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang. Pada umumnya mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Depresi ditandai dengan perasaan sedih yang psikopatologis, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju kepada meningkatnya keadaan mudah lelah yang sangat nyata sesudah bekerja sedikit saja, dan berkurangnya aktivitas.Temuan di lapangan yang menunjukan respons depresi sebagai mana yang disampaikan oleh KublerRoss (1969), ditemukan lewat salah satu pernyataan dari informan yang menyatakan, “saya benci diriku yang tak bisa menghentikan penyakitnya, sehingga dia harus meninggal diusia muda”. 23 Seseorang yang mengalami depresi biasanya menyalahkan bahkan membenci dirinya sendiri. Depresi adalah kemuraman hati (kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan). Orang yang mengalami depresi adalah orang yang amat menderita. h. Menerima kenyataan. Kubler-Ross (1969), dalam tulisannya menyatakan bahwa menerima kenyataan Adalah proses mencoba berdamai dengan diri sendiri dan pasrah untuk menerima keadaan yang tak dapat ditolak terhadap keadaan yang dialami oleh diri. bekerja sedikit saja, dan berkurangnya aktivitas. Temuan di lapangan yang menunjukan respons depresi sebagai mana yang disampaikan oleh Kubler-Ross (1969), ditemukan lewat salah satu pernyataan dari informan yang menyatakan, Contohnya, “kepergiannya menyisakan dukacita yang teramat dalam tetapi kami percaya pada penyertaan-Nya setiap saat bagi kami sekeluarga’’. Inilah tahap terakhir dari proses berduka yang dapat juga disebut sebagai titik akhir sejarah perjalanan kedukaan. Pada titik tersebut si penduka telah siap memasuki babak baru kehidupannya sekalipun tanpa orang yang dicintainya lagi. 24 i. Harapan Sekali pun di satu sisi, kematian orang-orang terdekat selalu menyisakan kehilangan dan dukacita yang berkepanjangan, namun di sisi lain dukacita merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk meringankan kehidupannya menghadapi kesedihan mendalam. Granger (1978) mengatakan bahwa kedukaan adalah nafas manusia yang merupakan gerakan yang simultan seperti ketika mengeluarkan udara yang kotor lalu kemudian menghirup udara yang bersih. Ada nafas dalam, sebagaimana ada duka yang dalam dan ringan (Rando, 1984). Hal tersebut nampak juga dari pandangan tentang pentingnya proses berduka bagi setiap individu yang mengalami kehilangan karena setelah itu mereka akan dengan harapanharapanbaru. Hal tersebut nampak antara lain dari ungkapan Contohnya “berharap setelah kepergiannya hidup kami lebih baik dan semakin mandiri dalam segala hal”. D.Tugas poses berduka Tugas dalam proses berduka diuraikan oleh Rando (1984) sebagai berikut: 1. Memutus ikatan psikososial terhadap orang yang dicintai dan pada akhirnya menciptakan ikatan baru 2. Menambah peran, keterampilan dan perilaku baru dan merevisi peran, keterampilan dan perilaku yang lama menjadi “suatu identitas dan kesadaran diri yang baru 3. Mengikuti gaya hidup yang sehat yang mencakup individu dan aktivitas 4. Mengintekgrasikan kehilangan ke dalam kehidupan. Hal ini tidak berarti akhir proses berduka telah dicapai tetapi “akomodasi” terjadi saat realitas kehilangan diintegrasikan ke dalam kehidupan. 25 Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian sepanjang proses dukacita adalah kompleksitas dukacita. Artinya apakah dukacita yang dialamai seseorang itu tertunda atau terselesaikan. E.Kompleksitas kedukaan Menurut Wiryasaputra (2003) kompleksitas kedukaan meliputi: a. Duka yang diselesaikan Dalam kondisi ini penduka menyadari bahwa ia sedang berduka, menerimanya sebagai pengalaman pribadi dan bersedia mengekspresikan perasaan yang muncul. Sikap terbuka menerima realitas adalah pintu masuk ke dalam proses penyembuhan. b. Duka yang belum diselesaikan Duka yang belum diselesaikan muncul sebagai konsekwensi pilihan penduka. Ketika menekan perasaannya ia akan mengalami duka yang tidak terselesaikan. Duka yang tidak terselesaikan tersebut, terdiri dari tiga kategori, yaitu a. Duka yang berkepanjangan b. Duka yang ditunda c. Duka yang tidak penuh Selepas ditinggalkan, masa berduka dimulai. Duka cita mungkin akan menjadi tidak sederhana meski seringkali dianggap hanya sebuah bentuk pernyataan emosi. Orang yang ditinggalkan merasakan rindu kepada yang telah meninggal dan berharap mereka akan hadir kembali. Benda atau tempat-tempat tertentu barangkali akan mengingatkan kepada orang yang meninggal dan merasa sedih lalu menangis. Kesunyian muncul seiring dengan kekhawatiran bahwa rasa kehilangan bertahan seumur hidup (Weisman,1974). 26 Videbeck (2008) menguraikan dimensi (respon) dan gejala individu yang berduka sebagai beriku: a. Respon kognitif : Gangguan asumsi dan keyakinan, mempertanyakan dan berupaya menemukan makna kehilangan, berupaya mempertahankan keberadaan orang yang meninggal. b. Respon emosional: Marah, sedih, cemas, kebencian,merasa bersalah, mati rasa, emosi yang berubah-ubah, penderitaan dan kesepian yang berat, keinginan kuat untuk mengembalikan ikatan dengan individu atau benda yang hilang, depresi, apapti, putus asa selama fase disorganisasi dan keputusasaan. Saat fase reorganisasi muncul rasa mandiri dan percaya diri. c. Respon spiritual: Kecewa dan marah pada Tuhan, menderita karena merasa ditinggalkan, tidak memiliki harapan dan kehilangan makna. d. Respon perilaku : Melakukan fungsi secara “otomatis”, menangis terisak atau tidak terkontrol, sangat gelisah, perilaku mencari, iritabilitas dan sikap bermusuhan, mencari atau menghindari tempat dan aktivitas yang dilakukan bersama orang yang telah meninggal, menyimpan benda berharga orang yang telah meninggal padahal ingin membuangnya. Mencari aktivitas dan refleksi selama fase reorganisasi. e. Respon fisiologis: Sakit kepala, insomnia, gangguan nafsu makan , berat badan turun, tidak bertenaga, palpitasi, gangguan pencernaan, perubahan sistim imun dan endoktrin. F.Faktor-faktor yang mempengaruhi dukacita Menurut Bowlby (1980) manusia secara naluriah memperoleh dan mempertahankan ikatan kasih sayang dengan orang terdekat melalui perilaku kedekatan. Perilaku kedekatan ini sangat penting bagi perkembangan dan 27 kelangsungan hidup seseorang yang mengalami kehilangan. Perilaku yang dilakukan untuk memperoleh dan mempertahankan kedekatan dapat mencakup mengingat, mengikuti, berteriak, menangis dan meratap. Dalam kehilangan perilaku kedekatan muncul dengan kuat sehingga gambaran peningkatan ansietas, penderitaan, mencari individu yang hilang dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan ikatan kasih sayang yang telah hilang. Berdasarkan pandangan di atas maka ritual ma’nenek dikaji melalui pendekatan Psikologi Indigenous dengan harapan dapat mengetahui alasan sesungguhnya yang mendasari perilaku dan mental orang Toraja yang bersifat pribumi, tidak dibawa dari daerah lain, dan didesain untuk masyarakatnya sendiri (Kim dan Berry, 1993). Pendekatan ini mendukung pembahasan mengenai pengetahuan, keahlian, kepercayaan yang dimiliki seseorang serta mengkajinya dalam bingkai kontekstual yang ada. Teori, konsep, dan metodenya dikembangkan secara indigenous disesuaikan dengan fenomena psikologi yang kontekstual. Sehingga dapat dihasilkan pengetahuan yang lebih teliti, sistematis, bersifat universal dan secara teoritis maupun empiris dapat dibuktikan tentang cara orang Toraja mengingat, berteriak, menangis dan meratap pada saat ritual tersebut berlangsung dan bagaimana mereka mempertahankan kelangsungan hidupnya setelah ditinggalkan. Menurut Wiryasaputra, (2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi dukacita, yaitu: a. Intensitas hubungan dengan yang hilang Hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat kedalaman guncangan emosi. Semakin signifikan peran orang yang hilang maka respon kedukaan juga akan semakin dalam dan kompleks b. Struktur kepribadian 28 Jika tipe kepribadian orang yang berduka tergantung pada orang yang hilang maka respon dukacitanya akan sangat dalam bahkan membuatnya tak berdaya. Sebaliknya, jika yang ditinggalkan adalah tipe kepribadian yang mandiri dan kuat maka dukacita yang dialami akan lebih ringan. Tidak semua orang yang berduka mengalami depresi. Orang yang memandang kematian sebagai hal yang wajar akan lebih mampu mengelola guncangan dukacita akibat kematian yang dialami. c. Sosio-Budaya Penduka Untuk memahami kedukaan seseorang sangat penting untuk mengerti iklim sosialnya sebab dukacita juga sangat dipengaruhi oleh sistem sosial. Jika lingkungan sosial memahami seluk beluk kedukaan dan menyediakan sarana pendukung kesembuhan pribadi maka penduka dapat segera pulih. Sebaliknya, jika kondisi masyarakat lokal melihat dukacita sebagai sesuatu yang negatif maka kedukaan dapat menjadi patologis. d. Nilai pribadi yang hilang Dukacita tidak langsung disebabkan oleh individu yang hilang melainkan karena nilai yang diberikan padanya. Semakin berharga orang yang hilang akan semakin dalam duka yang ditimbulkannya. e. Tingkat hubungan emosional Semakin tinggi nilai yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu maka akan semakin dalam pula hubungan yang diciptakan. Kedalaman kedukaan berbanding lurus dengan tingkat hubungan emosional seseorang dengan objek yang hilang, maka akan semakin kompleks dan berkepanjangan juga duka yang dialami. Sebaliknya, semakin dangkal atau atau renggang hubungan emosional seseorang 29 dengan sesuatu atau seseorang yang hilang maka akan semakin ringan dan sederhana duka yang dirasakan. f. Kebudayaan dan adat istiadat Pada dasarnya setiap kebudayaan telah memiliki perangkat untuk menolong masyarakatnya dalam menghadapi dukacita khususnya karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Pola pikir dan kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang berduka dalam relasi dengan lingkungannya akan mempengaruhi cara mereka merespon dukacitanya. Rasa duka dan mencintai adalah dua perasaan emosi yang serupa yang dialami seseorang. Jika seseorang sanggup untuk mencintai, maka seseorang tersebut juga memiliki rasa duka. Setiap orang, bagaimana pun, memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi kematian atau kehilangan. Bagi orang-orang yang tidak terlalu dikenal, rasa duka ini hanya berlangsung sebentar saja. Berbeda bila orang yang meninggal tersebut adalah seseorang yang memiliki hubungan emosi yang dekat, maka dapat timbul rasa duka yang sangat dalam (Tandjung, 1976). G. Pendekatan Psikologi Indigenous Karakteristik indigenous adalah sebuah pendekatan yang dapat didefenisikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku manusia yang asli, dirancang khusus untuk masyarakat setempat yang menjadi subyek penelitian sehingga budayanya dapat dipahami dalam bingkai acuannya sendiri. Pendekatan ini penulis pilih setelah membaca beberapa literatur tentang psikologi indigenous maupun hasil penelitian tentang keunikan budaya di beberapa daerah di Indonesia. Menurut penulis, pendekatan Indigenous tepat untuk menganalisis ritual ma’nenek yang merupakan fenomena unik yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memelihara 30 tradisi ini. Cara mereka mengekspresikan dukacita dan apa makna tradisi ini hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh rumpun keluarga yang memelihara tradisi ma’nenek. Berdasarkan observasi dan keikutsertaan dalam ritual dan juga melalui wawancara dengan para partisipan akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan tentang betapa pentingnya ritual ini bagi keluarga yang berduka. Penulis sendiri sebagai orang Toraja sangat asing dengan budaya ma’nenek karena tradisi ini tidak dikenal dalam keluarga penulis sekali pun para tetangga bahkan rumpun keluarga terdekat melaksanakan tradisi ini sejak dulu dari tahun ke tahun. Orang tua penulis bahkan sampai saat ini belum pernah mengikuti ritual ma’nenek. Psikologi Indigenous adalah suatu kajian ilmiah mengenai perilaku dan mental manusia yang bersifat pribumi, tidak dibawa dari daerah lain, dan didesain untuk masyarakatnya sendiri (Kim & Berry, 1993). Pendekatan ini mendukung pembahasan mengenai pengetahuan, keahlian dan kepercayaan yang dimiliki seseorang serta mengkajinya dalam bingkai kontekstual yang ada. Teori, konsep, dan metodenya dikembangkan secara indigenous disesuaikan dengan fenomena psikologi yang kontekstual. Tujuan utama dari pendekatan psikologi Indigenous adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih teliti, sistematis, bersifat universal dan secara teoritis maupun empiris dapat dibuktikan (Kim, Yang dan Hwang, 2006). Kemunculan psikologi indigenous tidak lepas dari kebimbangankebimbangan peneliti psikologi dari Asia, yang belajar psikologi di Barat, ketika mereka kembali dan mencoba untuk mengembangkan psikologi di negaranya, mereka menjumpai banyak kesulitan dan mulai mempertanyakan kembali validitas, universalitas, dan aplikabilitas dari teori-teori psikologi (Kim, 2000). Para peneliti tersebut berkesimpulan bahwa setiap budaya harus dipahami dari bingkai acuannya sendiri, termasuk konteks ekologi, sejarah, filosofi, dan agama yang ada (Kim, Yang dan Hwang, 2006). 31 Pendekatan psikologi indigenous mempertanyakan konsep universalitas dari teori-teori psikologi yang ada dan berusaha menemukan psikologi yang universal dalam konteks sosial, budaya, dan ekologi (Kim dan Berry, 1993; Kim, Yang, Huang (2006). Hal ini didukung dengan keterangan dari Neuman (1995), yang menyatakan tentang sejumlah penelitian menyebutkan bahwa teori-teori psikologi sebenarnya berkaitan dengan batasan budaya (culture-bound), nilai-nilai daerah (value-laden) dan dengan validitas yang terbatas. Psikologi Indigenous menyajikan suatu pendekatan dimana muatannya (makna, nilai dan kepercayaan) bersifat kontekstual (keluarga, sosial, budaya, dan ekologi) yang secara eksplisit menggabungkannya dalam desain penelitian (Kim, Yang dan Hwang, 2006). Pendekatan psikologi indigenous amat penting dilakukan di Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya , sebagaimana pernyataan Kim dan Berry (1993, p.76) berikut ini: “Indigenuous psychologies can be defined as the scientific study of human behaviour (or the mind) that is native, that is not transported from other regions, and that is designed for its people.” Kim, Yang dan Hwang (2006) mengidentifikasi sepuluh karakteristik psikologi indigenous sebagai berikut: 1. Indigenous Psychology menekankan pada penelaan fenomena psikologis dalam konteks keluarga 2. Indigenous Psychology dibutuhkan oleh semua kelompok-kelompok kultural, pribumi, etnik termasuk negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju. 3. Indigenous Psychology merupakan tradisi dari ilmu pengetahuan yang salah satu aspek pentingnya adalah menemukan metode-metode yang tepat untuk fenomena yang sedang diinvestigasi, oleh karenanya dianjurkan untuk menggunakan berbagai metode. 32 4. Diasumsikan bahwa hanya orang pribumi atau orang dalam di sebuah budaya yang dapat memahami fenomena indigenous dan kultural sedangkan orang luar hanya dapat memiliki pengetahuan yang terbatas. 5. Dalam indigenous psychology peran para penelitilah yang mampu menterjemahkan pengetahuan episodik menjadi bentuk-bentuk analitik agar dapat diuji dan diverifikasi. 6. Indigenous psychology adalah bagian dari tradisi ilmiah yang berusaha menemukan pengetahuan psikologis yang berakar pada konteks budaya. 7. Banyak pakar indigenous psychology yang mencari buku filsafat untuk menjelaskan fenomena indigenous. Namun analisis-analisis tersebut adalah filsafat spekulatif dan mereka masih harus didukung oleh buktibukti empiris. Meskipun mereka telah memberi informasi dasar dan kaya bagi pengembangan teori-teori formal, masih perlu diuji dan divalidasi secara empiris. 8. Indigenous psychology diidentikkan sebagai bagian dari tradisi ilmu budaya, dimana orang tidak sekedar bereaksi atau beradaptasi dengan lingkungan, tetapi mereka juga mampu memahami dan mengubah lingkungan, orang lain dan dirinya sendiri. 9. Indigenous psychology menganjurkan pengaitan antara humanitas dengan ilmu-ilmu sosial sehingga dapat memberikan pengetahuan dan insight yang berharga. 10. Dua titik awal penelitian dalam indigenous psychology yaitu indigenization from without (melibatkan teori, konsep yang sudah ada dan meodifikasinya agar cocok dengan budaya lokal) dan indigenization from within (teori, konsep dan metodologi dikembangkan secara internal dan informasi indigenous dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Walaupun semua orang berduka ketika kehilangan orang yang dicintai, namun ritual dan kebiasaan yang berkaitan dengan kematian bervariasi di 33 antara budaya. Setiap budaya mendefenisikan proses berduka dan mengintegrasikan kehilangan ke dalam hidup dengan cara yang konsisten dengan keyakinan mereka tentang kehidupan, kematian dan kehidupan akhirat. Aspek pengalaman tertentu dapat dianggap lebih penting pada suatu budaya, sedangkan pada budaya lain dianggap kurang penting (Shapiro, 1996). Hal ini nampak juga dalam ritual ma’nenek orang Toraja. Setelah berlangsungnya pemakaman selama kurang lebih setahun mereka merindukan suatu kesempatan untuk berkumpul bersama dimana mereka dapat mengungkapkan dukacita dengan mengenang, menangis, meratap, berteriak, menjemur dan membungkus tulang-tulang jenazah serta merawat lingkungan sekitar pemakaman sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga yang telah meninggal. Psikologi Indigenous juga menekankan pada penelaan fenomena psikologis dalam konteks keluarga. Diasumsikan bahwa hanya orang Toraja yang melaksanakan ritual tersebut yang benar-benar mengerti dan merasakan makna ritual bagi kelangsungan hidup mereka tanpa orang yang dikasihi lagi. Sedangkan orang luar termasuk orang Toraja yang tidak melaksanakannya hanya dapat memiliki pengetahuan yang terbatas. H. Suku Toraja Sebelum membahas tentang makna dan cara orang Toraja mengekspresikan dukacita dan kehilangan melalui ritual ma’nenek, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat mengenai suku Toraja serta konsepnya tentang kehidupan dan kematian. Toraja berasal dari kata “tau raya” yang berarti “orang besar”, atau “raja”, ; juga dari kata “To raa” dari kata to artinya “orang” sedangkan raa artinya “murah hati”. Tana Toraja yang terletak sekitar 400 km di utara Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan masih kerap diasosiasikan 34 dengan makna “tanah para raja”. Tana Toraja dikenal sebagai salah satu tujuan wisata yang unik di Indonesia. Selain alamnya yang sejuk dan berlembah, kebudayaan asli masyarakatnya menjadi daya tarik utama (The Guide Magazine; Pemda Tana Toraja dan Toraja Utara). Kebudayaan asli suku Toraja yang sampai saat ini masih dipegang kuat adalah kebudayaan mengenai ritual berkabung/pemakaman yang disebut dengan Rambu Solo’ dan ritual pengucapan syukur yang disebut Rambu Tuka’ (upacara syukur). Rambu Solo’ merupakan ritual yang berasal dari kepercayaan aluk to dolo (agama lokal) yang dulunya merupakan kepercayaan suku Toraja. Ajaran aluk to dolo memiliki konsep tersendiri tentang hidup dan mati, yaitu antara keduanya merupakan suatu kesinambungan proses kehidupan. Menurut Kobong (2009), makna kehidupan bagi orang Toraja adalah menjalani siklus kehidupan itu sendiri artinya kembali kepada kehidupan semula yang nyata, kehidupan di “seberang sana”. Sejak lahir bahkan sebelum lahir setiap manusia sudah menggenggam potensi-potensi kehidupan. Manusia terlahir ke dunia dengan tangan yang penuh potensi yang harus dikembangkan dalam kerangka hidup bersama . Konsepsi orang Toraja tentang kehidupan bersifat siklis artinya nilai-nilai kehidupan itu berhubungan dengan keseluruhan siklus kehidupan yang terdiri atas kelahiran, kehidupan dan kematian. Dari awal sampai akhir hingga yang akhir itu kembali ke awal. Namun gerak siklis ini tidak dapat berulang tetapi bersifat einmalig, berlangsung sekali saja. Pentingnya pelaksanaan ritus-ritus orang mati bagi orang Toraja dijelaskannya melalui proses seperti berikut: a. Kelahiran. Setelah kelahiran seorang bayi plasentanya dikubur dibawah tangga di sebelah timur rumah disertai doa agar ia secara fisik menjadi besar, semakin 35 bertumbuh dan semakin bijaksana sebagaimana pada pagi hari naik semakin tinggi. Penanaman plasenta juga mempunyai arti agar bayi itu tidak akan menjadi besar seperti seseorang yang plasentanya tidak ditanamkan, artinya agar ia menjadi bijak dalam tutur katanya dan tidak mengucapkan hal-hal yang bodoh. Orang berdoa memohon agar bayi itu tidak akan pernah melupakan lamunan lolona (kampung halamannya dan terutama tongkonan rumah keluarga-nya) termasuk adat istiadatnya. Seorang bayi yang baru lahir sudah membawa kerbaunya, babi, padi dan kekayaan lainnya di dalam genggamannya dan ia akan mati pula dengannya. Inilah dasar pemotongan hewan terutama kerbau pada upacara kematian orang Toraja yang dikenal dengan Rambu Solo’. Di sini menjadi jelas bahwa nilai-nilai yang paling disukai adalah kekayaan dan kedudukan baik, yang disimbolkan dengan penanaman plasenta pada sebelah timur rumah. Salah satu lagu untuk menidurkan (panglellenan= lullaby, ninabobo) anak perempuan berbunyi: kasalle lao meurang, lobo’ mekabumbu (agar kalau ia besar ia pergi menangkap udang di sawah) dan untuk anak laki-laki berbunyi: Kasalle tang diada’, lobo’ papatu inaa; undoloi sangbara’mu, untonda pada dadimmu (agar engkau menjadi besar dan dewasa melampaui sebayamu dalam kekuatan dan kebijaksanaan). Ritus pada kelahiran (misalnya penanaman plasenta) senantiasa dikaitkan dengan harapan-harapan yang terkandung dalam lagu menidurkan anak. Anak kecil ditempatkan dibawah pengawasan para dewa. b.Kehidupan. Dewasa berarti mencapai usia untuk dapat menikah. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan dalle’ (nasib) seseorang . Melalui pernikahan suami istri memperoleh keturunan artinya lolo tau (manusia) serta peluang untuk memperoleh lolo patuoan ( hewan) dan lolo 36 tananan (tanaman). Karena semua nilai berhubungan dengan persekutuan maka wajar jika anak-anak sering dijodohkan oleh orang tua bahkan oleh keluarga besar mereka. Pernikahan itu sendiri sudah ada dibawah pengawasan aluk yakni alukna Rampanan Kapa’ (adat pernikahan). Selain itu diperlukan jaminan untuk mengamankan pernikahan dari ketidaksetiaan (perceraian) yaitu kapa’ yakni jumlah denda (hukuman) yang harus dibayar oleh pihak yang bersalah dalam kasus perceraian . Besarnya denda itu sudah ditentukan sebelumnya menurut kedudukan dalam sistim tana’ (strata sosial). Rampanan Kapa’ memainkan peranan penting dalam kehidupan persekutuan bukan hanya untuk mengembangkan dalle’ atau mendapatkan keturunan melainkan juga untuk memelihara, mempererat atau memulihkan hubungan keluarga yang rusak. Sepasang suami istri secepat mungkin membangun rumah sendiri yang menjadi awal tongkonan atau batu a’riri (biasanya untuk rakyat jelata dan para budak), pusat bagi keturunan untuk mengamalkan kedamaian dan harmoni di dalam kerangka persekutuan komunitas. Tongkonan itu menjamin pelaksaan aluk dan adat terutama Aluk Rambu Solo’ (ARS) dan Aluk Rambu Tuka’ (ART). Tongkonan adalah persekutuan yang menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan ini tetapi lebih khusus untuk kehidupan di seberang sana. Umpasundun aluk, menyempurnakan aluk merupakan kewajiban tongkonan yaitu kewajiban seluruh anggota persekutuan yang berpusat pada tongkonan itu. Jika seseorang tidak ingin kehilangan jati diri maka ia harus mengidentifikasikan dirinya ke dalam tongkonan, sebab tongkonan adalah jati diri sosial seorang Toraja. Itu berarti ia harus ikut berpartisipasi dalam kewajiban-kewajiban terhadap tongkonan. 37 Sering orang muda bingung menghadapi sikap orang tua yang mengaku tidak mampu membayar uang kuliah mereka tetapi menerima beban yang sebenarnya tidak dapat ditanggung untuk ritus-ritus kematian menurut semboyan umpaden tae’na (mengadakan yang tidak ada). Para pemuda tidak memahami bahwa umpasundun aluk merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus dipenuhi untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kini dan disini bagi seluruh anggota persekutuan tetapi terlebih bagi yang sudah meninggal yang baginya ritus-ritus itu diselenggarakan. Nasib orang mati itu tergantung sepenuhnya pada pelaksanaan ritus, sedangkan para pemuda itu masih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dalle’ mereka. c.Kematian Menurut pemahaman orang Toraja maut hanyalah peralihan dari kehidupan ini ke dimensi eksistensi yang lain. Peralihan ini merupakan fase yang sangat menentukan bagi seluruh siklus kehidupan. Dalam fase ini manusia kembali ke titik awal kehidupan . Ritus-ritus yang ditentukan untuk peralihan ini sangat kompleks, tetapi struktur dasarnya senantiasa sama. Ritus-ritus untuk orang mati ditentukan oleh status sosial si mati. Kompleksitas ritus-ritus itu tidak menjadi masalah asal saja ketentuanketentuannya ditaati. Satu-satunya persoalan adalah apakah keluarga mempunyai harta yang dibutuhkan untuk melaksanakan ritus-ritus yang ditentukan? Setelah ketentuan terpenuhi yang meninggal itu dapat kembali ke dalam status semula dan menjadi leluhur yang didewakan atau makluk ilahi. Jika orang mati tidak dibalikan pesungna artinya jika ritus-ritus kematian tidak dilaksanakan baginya ia akan terus-menerus mengganggu atau mengutuki keturunannya. Tujuan akhir seluruh ritus-ritus kematian 38 adalah membali puang (kembali ke status ilahi, ke status semula), menjadi dewa atau makluk ilahi. Kebahagiaan di dunia ini hanya merupakan bagian pendahuluan dari kehidupan abadi. Dari situ munculnya pepatah orang Toraja pa’tondokan marendeng (marendeng = tempat tinggal abadi), artinya dunia ini hanyalah sebuah tempat perhentian; tempat tinggal yang abadi ada di “atas”, tempat tinggal para dewa, makhluk-makhluk ilahi dan para leluhur yang didewakan . Itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itulah setiap orang wajib berbuat sedapat mungkin untuk mencapai tujuan itu. Kalau perlu apa yang tidak ada harus dibuat menjadi ada, umpaden tae’ na. Untuk itu bila perlu orang berutang. Dapat dikatakan bahwa orang Toraja hidup untuk mati. Seringkali sangat sulit untuk mendapatkan uang guna membeli obat bagi seseorang yang sakit tetapi bila orang sakit itu meninggal maka pastilah keluarganya akan mengusahakan ritus baginya yang sesuai dengan tana’ (status) sosialnya. Dari sini nampak bahwa pelaksanaan ritus-ritus bagi orang mati itu berpengaruh besar terhadap cara hidup orang Toraja. Nilai-nilai hidupnya berorientasi baik pada kehidupan kini maupun pada kehidupan setelah kematian. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun sering kali kewajiban dalam ritus-ritus itu menjadi beban berat, bahkan tak terpikul. Dalam ritus itu mereka mempersembahkan hewan khususnya kerbau dan babi yang harganya sangat mahal. Persembahan itu mempunyai nilai eskhatologis dalam kehidupan orang Toraja. Artinya kehidupan dibalik kematian mempengaruhi atau paling tidak mewarnai kehidupan mereka saat ini. Korban persembahan diberikan dalam kerangka do ut des, artinya mereka mempersembahkan sesuatu dalam relasi dengan para dewa dan para leluhur mereka agar dewa dapat memberikan berkat yang lebih besar dan lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dalam ritus ma’karoen atau ma’pakande to matua yakni ritus untuk membawa persembahan kepada leluhur sebagai 39 penghormatan dan ungkapan persekutuan dengan mereka. Hal tersebut dapat dijumpai pada ritual ma’nenek. Kehidupan saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di seberang sana. Tanpa para leluhur, persekutuan dianggap tidak lengkap. Oleh karena itu hubungan dengan mereka harus terus terpelihara. I. Ritual Ma’nenek Menurut tradisi lisan orang Toraja, ma’nenek berarti mengganti pakaian leluhur (nenek). Sekalipun dalam kenyataan ritual ini tidak dilakukan hanya pada jenasah orang tua/ nenek saja melainkan semuanya. Ma’nenek ialah upacara di sekitar kubur dengan membersihkan lingkungan sekitar kuburan, memberikan persembahan kepada arwah leluhur, memberi bungkus baru kepada jenazah atau mengganti pakaian tau-tau yang sudah lapuk. Ritual Ma’ Nene’ oleh masyarakat setempat juga dianggap sebagai wujud kecintaan mereka pada para leluhur, tokoh dan kerabat yang sudah meninggal dunia. Mereka tetap berharap, arwah leluhur menjaga mereka dari gangguan jahat, hama tanaman, juga kesia-siaan hidup (Sarira, 1996). Masih ada juga yang memberikan "sesuatu" seperti uang, kain, tembakau untuk dipakai di"sana". Pada saat memberikan benda-benda itu mereka berbicara sebagaimana layaknya memberikan sesuatu kepada orang yang masih hidup. Misalnya dengan mengatakan, "Kain ini dari cucumu yang sedang merantau, dia sangat merindukanmu tetapi tidak sempat datang menjengukmu...; mamali’ liuna’ ...sae komi lan pangimpingku (saya sangat rindu datanglah dalam mimpiku), pamatoto’na’ mutampe misa-misa” (kuatkan aku karena kau tinggalkan sendiri; 28-8-2013) dan lain-lain. Upacara ini dilaksanakan sesudah panen sehubungan dengan keyakinan bahwa keberhasilan atas panen itu adalah merupakan berkat dari leluhur yang selalu memperhatikan kehidupan keturunannya. 40 J. Asal Usul ritual Ma’nenek Berdasarkan cerita rakyat turun temurun ritual ma’ nenek berawal dari sebuah desa yang bernama Baruppu’ (di daerah ini ma’nenek dilaksanakan sekali dalam tiga tahun). Pada zaman dahulu terdapatlah seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek. Saat sedang berburu di kawasan hutan pegunungan Balla, bukannya menemukan binatang hutan, ia malah menemukan jasad seseorang yang telah lama meninggal dunia. Mayat itu tergeletak di bawah pepohonan, terlantar, tinggal tulang-belulang. Merasa kasihan, Pong Rumasek kemudian merawat mayat itu semampunya. Dibungkusnya tulang-belulang itu dengan baju yang dipakainya, lalu diletakkan di areal yang lapang dan layak. Setelah itu, Pong Rumasek melanjutkan perburuannya. Tak disangka-sangka semenjak kejadian itu, setiap kali Pong Rumasek berburu ia selalu memperoleh hasil yang banyak. Binatang hutan seakan digiring kepadanya. Bahkan sesampainya di rumah, Pong Rumasek mendapati tanaman padi di sawahnya pun sudah menguning, bernas dan siap panen sebelum waktunya. Dia sangat bahagia dan yakin bahwa segenap peruntungan itu diperolehnya berkat belas kasih dari leluhur karena merawat mayat tak bernama yang ditemukannya saat berburu. Sejak itulah, Pong Rumasek dan masyarakat Baruppu melaksanakan ritual ma’nenek. I. Peraturan dan prosesi Ma’nenek a. Peraturan Ma’nenek Dalam pelaksanaan ritual Ma’nenek terdapat aturan-aturan tak tertulis yang mengikat orang Toraja yang melaksanakannya (Arung, 1999) antara lain: - Jika seorang istri atau suami meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggal tidak boleh kawin lagi sebelum mengadakan ma’ menek. Kecuali dengan melakukan upacara ma’tengkai/ullambanni kalo’ (secara harfiah artinya melangkahi parit). Orang tersebut sudah boleh 41 bertunangan atau diikat secara adat tetapi belum boleh tinggal bersama. Ketentuan adat tersebut dimaksudkan agar janda atau duda jangan dulu meninggalkan rumahnya terlalu jauh karena ia masih dalam keadaan berduka yang sangat dalam. Hal itu ditandai dengan memakai pakaian serba hitam. Selama masa penantian itu mereka harus menjaga segala tindak tanduknya di dalam pergaulan seharihari. Apabila mereka kedapatan melakukan sesuatu yang tidak pantas maka perbuatannya itu akan dikutuk oleh seluruh masyarakat sekampungnya dan akan dihukum berdasarkan ketentuan-ketentuan adat, yakni dengan berbondong-bondong mengerumuni rumah si pelaku untuk menombak babinya sampai mati sebagai korban perdamaian. - Pada saat pelaksanaan ma’ nenek, para perantau pulang kampung demi menghormati leluhurnya. Mereka percaya bahwa apa bila ritual ma’ nenek tidak dilaksanakan maka leluhur juga tidak akan menjaga sehingga mereka tidak akan berhasil di tanah orang bahkan musibah akan melanda, penyakit akan menimpa warga, sawah dan kebun tak akan menghasilkan padi yang bernas dan tanaman yang subur. - Ma’nenek hanya boleh dilaksanakan setelah masa panen pada saat alla’ padang /lo’bang padang ( tanah lagi kosong). b. Prosesi Ma’nenek Sehari sebelum pelaksanaan ritual, pintu-pintu kuburan sudah dibuka dan dijaga semalam suntuk oleh keluarga. Di situ mereka makan dan minum sebagaimana layaknya di rumah sendiri. Keesokan harinya pada saat pelaksanaan ritual peti-peti mati dikeluarkan dari makam-makam atau liang batu dan diletakkan di arena upacara. Di sana, sanak keluarga dan para kerabat sudah berkumpul. Secara perlahan, mereka mengeluarkan jenazah (baik yang masih utuh maupun yang 42 tinggal tulang-belulang). Mengeluarkan dari peti, menjemur beberapa saat lalu mengganti busana yang melekat di tubuh jenazah dengan yang baru. Mereka memperlakukan sang mayat seolah-olah masih hidup dan tetap menjadi bagian dari keluarga besar. Menurut Indo’ Limbong, pada zaman dahulu upacara ma’nenek di To’Nakka’ dilakukan dengan bermalam satu malam dikuburan, membuat pondok-pondok beratapkan daun nira dan daun tembakau dijadikan sebagai dinding. Keluarga yang berduka membuat patung – patung dari bola (bambu muda) disusun rapi, setelah itu dilanjutkan dengan ma’ badong dan ma’ dondi’ semalam suntuk diterangi sulo (obor) . Rasa dukacita dan kehilangan dianggap belum selesai oleh karena itu keesokan harinya seekor kerbau dipotong lagi dan dagingnya yang masih mentah dijadikan rebutan sampai habis. Setelah itu barulah seluruh proses dukacita dianggap selesai. Sementara menurut To minaa nek Lumbaa pada zaman dahulu ritual ma’nenek berlangsung selama 3 hari. Hari pertama pintu-pintu kuburan dibuka, hari kedua mangallo (menjemur) jenazah dan bungkusan tulang-tulang dikeluarkan untuk dijemur kemudian ma’kassa’i (mengganti pakaian/kain pembungkus jenazah). Hari ketiga merupakan saat untuk ma’pakande (memberi makan leluhur). Mereka yang sudah meninggal harus diberi makan terlebih dahulu dan tidak boleh sembarangan, daging yang terbaik dipilih untuknya, tidak boleh sembarang. Selain itu nek Tonga’ (mantan to minaa) juga mengatakan bahwa pada saat ritual pakaian yang dikenakan tidak boleh terlalu bagus, tidak boleh warna kuning (sukacita) dan warna hitam (kedukaan)...”pokoknya biasa saja”. 43 44

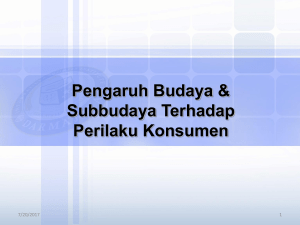






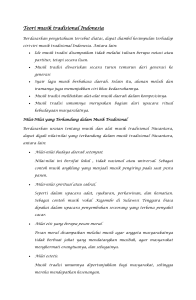
![Emosi [Compatibility Mode]](http://s1.studylibid.com/store/data/000960065_1-f12478d060f47c3497a4fc0ec98cf6da-300x300.png)