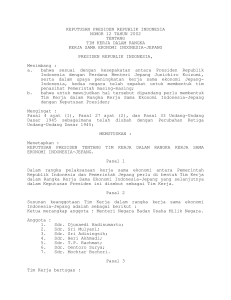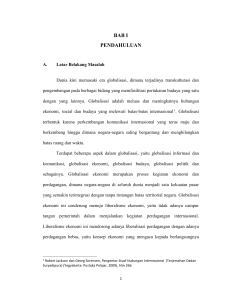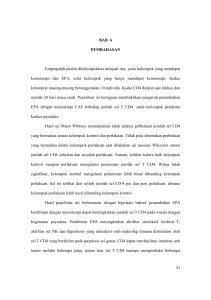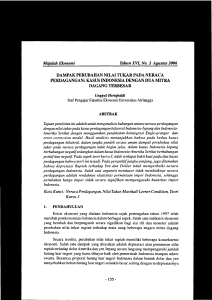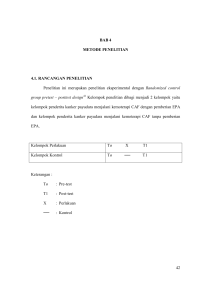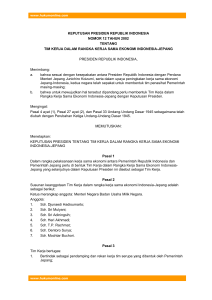Kerja Sama Indonesia-Jepang
advertisement

Kerja Sama Indonesia-Jepang Syamsul Hadi Kompas : 20 Agustus 2007 Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) Indonesia-Jepang ditandatangani hari ini, Senin (20/8). Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, dengan perjanjian ini Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ekspor beraneka produk ke Jepang, selain meningkatkan investasi Jepang di Indonesia. EPA Indonesia-Jepang mencakup tiga hal utama dalam perjanjian perdagangan bebas, yaitu perdagangan barang (trade in goods), pelayanan (service), dan penanaman modal (investment). Perjanjian ini akan berlaku efektif November mendatang. Hasil kesepakatan EPA diharapkan akan meningkatkan total ekspor Indonesia sekitar 4,68 persen dari total ekspor sebelumnya. Jepang pun akan menghapuskan bea tarif sebesar 9.275 item tarif dalam perdagangan barang dan jasa. EPA ini diharapkan akan meningkatkan kesempatan bisnis sebesar 65 miliar dollar AS pada tahun 2010 (IGJ, 2007). "Merayu" Jepang Penandatanganan EPA ini merupakan tonggak penting upaya pemerintah untuk terus meningkatkan investasi Jepang ke Indonesia. Hampir tidak terhitung jumlah kunjungan dan promosi guna mengundang investasi Jepang, dari presiden, wapres, menteri, birokrat, sampai organisasi bisnis. Juga telah dibentuk Joint Forum on Investment untuk kepentingan serupa. Tampaknya pemerintah ingin "mengembalikan" kedudukan istimewa Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia sepanjang masa Orde Baru. Tahun 1997 investasi Jepang mencapai 5,3 miliar dollar AS, dan turun menjadi 635 juta dollar AS tahun 2002, naik secara moderat menjadi 1,68 miliar dollar AS tahun 2004. Tahun 2005, Indonesia hanya di urutan ke-8 dari sejumlah negara yang menjadi tujuan investasi Jepang. Tahun 2006 Indonesia turun ke urutan ke-9. Obsesi "mengembalikan" posisi Jepang sebagai investor terbesar di Tanah Air tampaknya tidak mudah dicapai. Di tengah gencarnya kunjungan dan promosi bisnis ke Jepang, nilai investasi Jepang pada Januari-November 2006 mengalami penurunan 61,3 persen dibandingkan dengan nilai investasi Jepang pada periode sama tahun 2005 (Kompas, 6/12/2006). Persepsi Jepang atas iklim investasi di Indonesia tecermin dari penilaian resmi Japan External Trade Organization (Jetro) terhadap iklim investasi di negara-negara ASEAN. Tahun 2006, dengan menimbang variabel-variabel seperti transparansi aturan investasi, risiko nilai tukar, dan stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia hanya memperoleh skor -0,34. Skor negatif ini jauh lebih rendah daripada Malaysia dan Thailand yang sama-sama mendapat skor 0,43. Skor Indonesia bahkan masih berada di bawah Filipina (0,12) dan Vietnam (-0,01). Tampaknya pemerintah dan investor Jepang tidak cukup mempan "dirayu" dengan kunjungan resmi dan pidato indah para pemimpin Indonesia. Dalam konteks ini, telah lama ilmuwan politik Barat menulis, sektor pemerintah dan swasta Jepang, dengan sinis mereka namai Japan Incorporated, seakan berdiri sebagai kesatuan tunggal yang senantiasa berjalan seiring-seirama dalam arena ekonomi antarbangsa. Berkaca dari pengalaman Gencarnya upaya Indonesia "merayu" Jepang agar berinvestasi di Indonesia di satu sisi justru memperlemah bargaining position Indonesia. Ketika Presiden Yudhoyono menyatakan pentingnya mempercepat penyelesaian perundingan EPA Indonesia-Jepang November 2006, Perdana Menteri Shinzo Abe dengan gesit "menyambar" dengan statement bahwa untuk itu Indonesia harus menjamin pasokan gas alam untuk Jepang, selain segera menyelesaikan Undang-Undang Penanaman Modal. Ketergantungan Jepang pada gas alam Indonesia dengan pintar "dimainkan" Abe pada momentum yang tepat. Tidak heran, penandatanganan EPA dilakukan berbarengan dengan penandatangan proyek di bidang industri gas alam dan minyak bumi, yang jelas-jelas jadi kepentingan Jepang. Di sisi lain, Indonesia telah berusaha "menekan" Jepang untuk memberikan technical assistance di bidang energi, manufaktur, agrikultur, dan promosi UKM, selain berupaya membuka pasar tenaga kerja semi terampil di Jepang. Jepang menyepakati proyek-proyek capacity building untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu produsen Indonesia mencapai standar yang diinginkan untuk memasuki pasar Jepang. Dalam tingkatan tertentu, upaya Indonesia ini mirip yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tahun 1980-an. Dengan Look East Policy-nya, Mahathir mengumumkan keinginan agar Jepang berpartisipasi aktif sebagai investor utama sekaligus "pembimbing" pembangunan ekonomi Malaysia. Sayang, Mahathir harus kecewa. Alih-alih membuktikan komitmen untuk "membangun kapasitas" ekonomi Malaysia, Jepang malah terkesan teguh berpijak pada prinsip business is business. Barangkali "keengganan" Jepang untuk benar-benar "memajukan" Malaysia dapat dimengerti dengan merujuk pengalaman Jepang di Korsel, yang kini menjadi kompetitor yang andal di sektor manufaktur, setelah sekian lama belajar teknologi dan memanfaatkan modal Jepang untuk industrialisasi nasionalnya. Malaysia, China, dan Korsel adalah contoh negara yang dengan cerdik memanfaatkan kehadiran modal asing untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah ekonominya. Secara pintar, kehadiran modal asing, termasuk modal Jepang, diletakkan dalam agenda pembangunan domestik jangka pendek, yaitu mengurangi pengangguran dan menstimulus pertumbuhan. Arus deras modal Jepang tidak menghentikan kesungguhan mereka membangun "pohon industri" sebagai tiang ekonomi bangsa jangka panjang. Mereka insaf, kapan pun modal Jepang bisa pergi bila melihat ada negara lain yang lebih menjanjikan keuntungan. Ketika itu benar-benar terjadi, negeri-negeri itu telah memiliki sektor-sektor andalan yang dapat mengompensasi "ruang kosong" yang ditinggalkan modal Jepang. Bagaimana dengan Indonesia? Syamsul Hadi Pengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI; Executive Board pada Network of East Asian Studies (NEAS), Tokyo