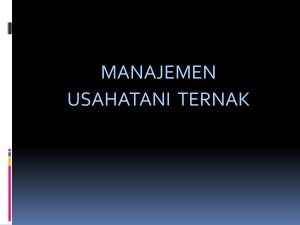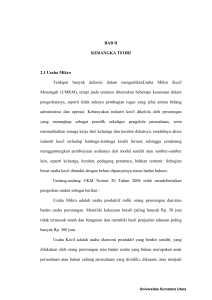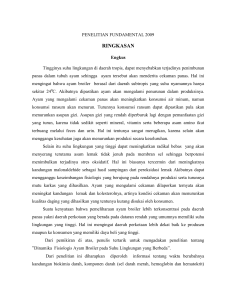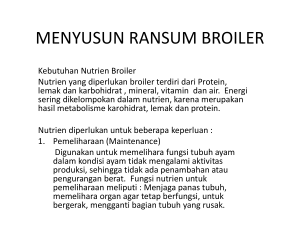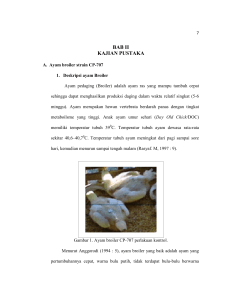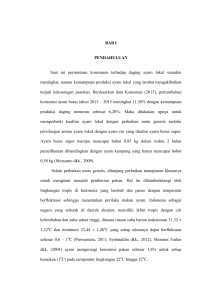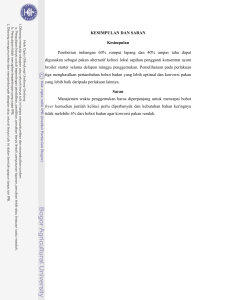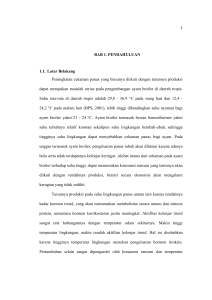persentase karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler
advertisement

PERSENTASE KARKAS, LEMAK ABDOMINAL, DAN ORGAN DALAM AYAM BROILER YANG DIBERI RANSUM DENGAN PENAMBAHAN CASSABIO SKRIPSI GAGAH HENDRA WIJAYA DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010 RINGKASAN Gagah Hendra Wijaya. D14062501. 2010. Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Organ Dalam Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Penambahan Cassabio. Skripsi. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ir. Iman Rahayu Hidayati Soesanto, MS. Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc. Pakan ayam broiler yang saat ini dijual di pasaran masih mengandalkan impor dari luar negeri sehingga harganya relatif mahal karena mengikuti harga pasar dunia yang selalu berfluktuatif dan ketersediaannya terbatas. Pakan alternatif yang berkualitas, murah, dan jumlahnya tersedia banyak di Indonesia diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Campuran antara onggok, urea, amonium sulfat, dan zeolit yang difermentasi dengan jamur Aspergillus niger atau yang disebut dengan cassabio merupakan salah pakan alternatif yang digunakan dalam ransum ayam broiler sehingga dapat menghasilkan karkas yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan 40 ekor ayam broiler strain Ross yang berumur 35 hari. Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima taraf perlakuan dan empat ulangan (setiap ulangan menggunakan sampel sebanyak dua ekor ayam broiler). Perlakuan terdiri atas pemberian ransum C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, dan C40 : cassabio 40%. Hasil data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis ragam (Analysis of Varience/ANOVA) dan bila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Tukey (Gaspersz, 1991). Peubah-peubah yang diamati terdiri atas bobot hidup akhir, persentase karkas, lemak abdominal, hati, jantung, ginjal, pankreas, limpa, rempela, panjang relatif duodenum, jejunum, ileum, seka, dan usus besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan cassabio hingga taraf 40% berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal dan panjang relatif usus besar (P<0,05) namun tidak berpengaruh terhadap bobot hidup akhir, persentase karkas, hati, jantung, ginjal, pankreas, limpa, rempela, panjang relatif duodenum, jejunum, ileum, dan seka. Berdasarkan kandungan lemak abdominal yang lebih sedikit sehingga lebih disukai oleh konsumen, sebaiknya kadar cassabio yang dicampurkan dalam ransum ayam broiler hingga taraf 20%. Kata-kata kunci : ayam broiler, cassabio, karkas, lemak abdominal, organ dalam ABSTRACT Carcass, Abdominal Fat, and Internal Organs Percentages of Broiler Chicken Which Fed by Cassabio Wijaya, G.H., H.S. Iman Rahayu, and A. D. Lubis This research was carried out to study the effect of feeding cassabio (fermented cassava pulp-zeolit-urea-amonium sulphate by Aspergillus niger) on carcass, abdominal fat, and internal organs of broiler. Fourty broilers of 35 days old were used in completely randomized design with five treatments and four replications. The treatment diets were: C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, and C40 : cassabio 40%. Variables observed were final body weigth, percentage of carcass, abdominal fat, liver, heart, kidney, pancreas, spleen, gizzard, relative length of duodenum, jejunum, ileum, seca, and large intestine. The data were analyzed by using Analysis of Varience (ANOVA) and significant results were followed by Honestly Significant Difference Test (Gaspersz, 1991). The result showed that there were no significantly different on final body weigth, percentage of carcass, liver, heart, kidney, pancreas, spleen, gizzard, relative length of duodenum, jejunum, ileum, and caeca. However, there were significantly different (P<0,05) in percentage of abdominal fat and relative length of large intestine. Due to abdominal fat content, it is recommended that 20% of cassabio in ration can be as an alternative local feed. Keywords: broiler, cassabio, carcass, abdominal fat, internal organs PERSENTASE KARKAS, LEMAK ABDOMINAL, DAN ORGAN DALAM AYAM BROILER YANG DIBERI RANSUM DENGAN PENAMBAHAN CASSABIO GAGAH HENDRA WIJAYA D14062501 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010 Judul : Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Organ Dalam Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Penambahan Cassabio Nama : Gagah Hendra Wijaya NIM : D14062501 Menyetujui, Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota, Prof. Dr. Ir. Iman Rahayu H.S., MS. NIP. 19590421 198403 2 002 Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc. NIP. 19670103 199303 1 001 Mengetahui, Ketua Departemen, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Prof. Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Agr.Sc. NIP. 19591212 198603 1 004 Tanggal Ujian: 2 Nopember 2010 Tanggal Lulus: RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Oktober 1987 di Bandung, Jawa Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Drs. Nur Hendaya dan Dra. Wijayanti. Penulis mengawali pendidikan dasar tahun 1994 di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Bandung dan diselesaikan pada tahun 2000. Pendidikan menengah pertama dimulai pada tahun 2000 dan diselesaikan tahun 2003 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandung. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandung pada tahun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2006. Penulis diterima di Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis diterima di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB pada tahun 2007. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi yaitu sebagai wakil ketua BEM Fapet IPB periode 2008-2009, wakil ketua Paduan Suara Fapet IPB (Gradziono Simphonia) periode 2007-2009, anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Bandung (PAMAUNG) periode 2006-2008, anggota Paduan Suara IPB (Agriaswara) tahun 2006, staf PSDM rohis Fapet IPB (FAMM Al An’aam) tahun 2007, divisi Budaya, Olahraga, dan Seni BEM Fapet IPB periode 2007-2008 dan bendahara IPTP 43 Fapet IPB periode 2007-2010. Penulis pernah mengikuti magang di KPBS Pangalengan tahun 2008 dan BIB Lembang tahun 2009. Penulis melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) yang didanai DIKTI dengan judul Usaha Budidaya Puyuh Petelur Omega 3 periode 2009-2010 dan menjadi peserta Program Mahasiswa Wirausaha IPB dengan usaha Budidaya Puyuh Petelur Omega-3 Menggunakan Sistem Zero Waste pada tahun 2010. Penulis bekerja sebagai manajer utama di peternakan puyuh petelur (Kahfi Group) tahun 2009-sekarang dan sebagai bendahara di peternakan ayam broiler (Abadi Farm) tahun 2010-sekarang. Penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik tahun 2008 dan BBM tahun 2009 serta 2010. Penulis aktif mengikuti kegiatan pelatihan seperti LES (Leadership and Enterpreneurship School) yang diselenggarakan BEM KM IPB tahun 2006-2007, pelatihan Soft Skill Fakultas Peternakan IPB tahun 2007, dan BEST (Building Enterpreneurship Student) Fakultas Peternakan IPB pada tahun 2009-2010. KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Organ Dalam Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Penambahan Cassabio yang ditulis berdasarkan hasil penelitian pada bulan Juli hingga September 2009. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Rasulullah SAW yang telah mengantarkan seluruh umat muslim menuju cahaya kebenaran dan ketaqwaan. Penelitian ini dimulai dari pembuatan pakan cassabio, pemeliharaan ayam hingga berumur 35 hari, pemanenan, dan pengamatan karkas, lemak abdominal, serta organ dalam ayam broiler. Penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan untuk analisis ransum dan Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Unggas Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor untuk pemeliharaan, pemanenan, dan pengamatan ayam broiler. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi persentase karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler yang diberi ransum dengan penambahan berbagai taraf cassabio. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Penulis berharap akan banyak masukan yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi baru dalam dunia peternakan dan dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Bogor, Desember 2010 Penulis DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN ......................................................................................... i ABSTRACT............................................................................................ ii LEMBAR PERNYATAAN .................................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................... iv RIWAYAT HIDUP ................................................................................ v KATA PENGANTAR ............................................................................ vi DAFTAR ISI........................................................................................... vii DAFTAR TABEL................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN........................................................................... xi PENDAHULUAN .................................................................................. 1 Latar Belakang ............................................................................. Tujuan .......................................................................................... 1 2 TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 3 Ayam Broiler ............................................................................... Karkas Ayam ............................................................................... Lemak Abdominal ....................................................................... Organ Dalam ................................................................................ Hati.................................................................................. Jantung ............................................................................ Ginjal .............................................................................. Pankreas .......................................................................... Limpa .............................................................................. Rempela .......................................................................... Usus Halus ...................................................................... Usus Buntu (Seka) .......................................................... Usus Besar ...................................................................... Onggok-Urea-Zeolit Fermentasi ................................................... 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 11 MATERI DAN METODE ...................................................................... 13 Lokasi dan Waktu ........................................................................ Materi ........................................................................................... Rancangan Percobaan .................................................................. Peubah yang Diamati ................................................................... Prosedur ....................................................................................... 13 13 15 16 17 HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 20 Evaluasi Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler .............. 20 Bobot Hidup Akhir ......................................................... Persentase Karkas ........................................................... Persentase Lemak Abdominal ......................................... Evaluasi Organ Dalam Ayam Broiler ........................................... Persentase Hati ................................................................ Persentase Jantung .......................................................... Persentase Ginjal ............................................................. Persentase Pankreas ........................................................ Persentase Limpa ............................................................ Evaluasi Saluran Pencernaan Ayam Broiler ................................. Persentase Rempela ......................................................... Panjang Relatif Duodenum ............................................. Panjang Relatif Jejunum ................................................. Panjang Relatif Ileum ...................................................... Panjang Relatif Seka ....................................................... Panjang Relatif Usus Besar ............................................. 20 21 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 32 Kesimpulan ................................................................................. Saran ........................................................................................... 32 32 UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................. 33 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 34 LAMPIRAN............................................................................................ 37 viii DAFTAR TABEL Nomor Halaman 1. Komposisi Zat Gizi Onggok dari Beberapa Sumber Berdasarkan Bahan Kering ..................................................................................... 11 2. Komposisi Bahan dan Kandungan Gizi Ransum Penelitian .............. 14 3. Hasil Analisa Kandungan Zat Makanan Onggok dan Cassabio Berdasarkan Persentase Bahan Kering .............................................. 15 4. Evaluasi Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler .................... 20 5. Evaluasi Organ Dalam Ayam Broiler ................................................ 23 6. Evaluasi Saluran Pencernaan Ayam Broiler ...................................... 27 DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Alur Proses Pembuatan Cassabio .................................................... 17 2. Alur Proses Pemanenan dan Pengamatan Ayam Broiler ................. 19 DAFTAR LAMPIRAN Nomor Halaman 1. Hasil ANOVA Bobot Hidup Akhir ................................................. 38 2. Hasil ANOVA Persentase Karkas ................................................... 38 3. Hasil ANOVA Persentase Lemak Abdominal................................. 38 4. Hasil Uji Tukey Persentase Lemak Abdominal ............................... 38 5. Hasil ANOVA Persentase Hati ........................................................ 39 6. Hasil ANOVA Persentase Jantung .................................................. 39 7. Hasil ANOVA Persentase Ginjal ..................................................... 39 8. Hasil ANOVA Persentase Limpa .................................................... 39 9. Hasil ANOVA Persentase Pankreas ................................................ 39 10. Hasil ANOVA Persentase Rempela ............................................... 40 11. Hasil ANOVA Panjang Relatif Duodenum ..................................... 40 12. Hasil ANOVA Panjang Relatif Jejunum ......................................... 40 13. Hasil ANOVA Panjang Relatif Ileum ............................................. 40 14. Hasil ANOVA Panjang Relatif Seka ............................................... 40 15. Hasil ANOVA Panjang Relatif Usus Besar ..................................... 41 16. Hasil Uji Tukey Panjang Relatif Usus Besar ................................... 41 PENDAHULUAN Latar Belakang Ayam broiler merupakan ternak yang memiliki banyak keunggulan diantaranya memiliki kandungan gizi yang lengkap, bibit mudah diperoleh, mudah dalam pemeliharaan, dan produksi karkas yang tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan karkas broiler yang baik yaitu dengan pemberian pakan yang berkualitas. Pakan yang saat ini dijual di pasaran masih mengandalkan impor sehingga harganya relatif mahal karena mengikuti harga pasar dunia yang selalu berfluktuatif dan ketersediaannya terbatas. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencari pakan lokal alternatif yang jumlahnya melimpah di Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ayam, salah satunya adalah onggok. Onggok merupakan limbah hasil pengolahan tapioka yang belum termanfaatkan secara optimal. Menurut Haroen (1993), onggok yang dihasilkan dari proses pengolahan mencapai 5%-15% dari bobot ubi kayu. Kelebihan onggok adalah harganya murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak, akan tetapi kandungan proteinnya kurang dari 2% dan serat kasarnya mencapai 35%, sehingga jarang dimanfaatkan oleh masyarakat (Pandey et al., 2000). Proses fermentasi menggunakan Aspergillus niger, urea, amonium sulfat, dan zeolit mampu meningkatkan kandungan protein dan menurunkan serat kasar onggok. Kombinasi kompleks fermentasi terbaik berdasarkan kandungan zat makanannya adalah penggunaan onggok 94,5%, urea 3%, dan zeolit 2,5% dari BK onggok. Onggokurea-zeolit yang difermentasi dengan Aspergillus niger meningkatkan protein kasar menjadi 14% (Lubis et al., 2007). Penelitian Pitriyatin (2010) menunjukkan nilai protein kasar dan nilai energi yang dihasilkan dari onggok fermentasi lebih tinggi daripada onggok tanpa fermentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, cassabio dapat dijadikan sebagai salah satu pakan alternatif yang ditambahkan pada pakan ayam broiler karena kandungan nutrisinya baik dan bahan baku yang tersedia cukup banyak di Indonesia. Evaluasi akhir ayam broiler yang diberi ransum dengan penambahan cassabio perlu dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan cassabio terhadap kualitas karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persentase karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler yang diberi ransum dengan penambahan berbagai taraf cassabio. 2 TINJAUAN PUSTAKA Ayam Broiler Ayam broiler merupakan galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki karakteristik ekonomi dan pertumbuhannya cepat sebagai penghasil daging, konversi ransum rendah, dapat dipotong pada umur muda, dan menghasilkan kualitas daging yang berserat lunak (Bell dan Weaver, 2002). Ayam broiler mempunyai tekstur kulit dan daging yang lembut serta tulang dada yang merupakan tulang rawan fleksibel. Kondisi ayam broiler yang baik dapat tercapai bila peternak memiliki pengetahuan mengenai pembibitan, pakan, dan manajemen yang baik (Ensminger et al., 1992). Faktor–faktor yang mempengaruhi bobot hidup ayam yaitu konsumsi ransum, kualitas ransum, jenis kelamin, lama pemeliharaan, dan aktivitas. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kebutuhan nutrisi ayam broiler pada umur yang berbeda (Soeparno, 1994). Bobot badan ayam broiler mengalami peningkatan yang cepat pada minggu awal penelitian hingga mencapai puncak pertumbuhan umur enam hingga tujuh minggu, setelah itu bobot ayam akan menurun (Bell dan Weaver, 2002). Penelitian Lubis et al. (2007) yang memelihara ayam broiler hingga berumur 42 hari memperoleh bobot hidup akhir 1.380-1.596,67 gram. Penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial pada ayam broiler hingga berumur 42 hari memperoleh bobot hidup akhir sebesar 1.132-1.658 gram. Karkas Ayam Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki, dan organ dalam. Persentase bobot karkas digunakan untuk menilai produksi ternak daging. Faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan dan komposisi tubuh yang meliputi distribusi berat, komposisi kimia, dan komponen karkas. Faktor nutrisi, umur, dan laju pertumbuhan juga dapat mempengaruhi komposisi bobot karkas dan persentase karkas yang biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya bobot hidup ayam. Penurunan terjadi pada persentase bagian non karkas seperti darah, usus halus, dan organ vital (Soeparno, 1994). Soeparno (1994) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi persentase bobot karkas ayam broiler adalah persentase bobot hidup. Persentase karkas merupakan perbandingan bobot karkas dengan bobot hidup, sehingga bobot hidup yang besar akan diikuti pula oleh bobot karkas yang besar begitupun sebaliknya. Leeson dan Summers (2000) melaporkan bobot karkas broiler umur 42 hari adalah 1.128,4-1.523,2 gram atau 64,70%-71,20% dari bobot hidupnya. Penelitian yang dilakukan Noormasari (2000) dengan taraf cassabio mencapai 15% memperoleh bobot karkas 955-1.100 gram atau 68,89%-70,78% dari bobot hidup. Penelitian yang dilakukan Dewi (2007) memperoleh bobot karkas 731-1.135 gram atau 63,79%-67,78% dari bobot hidup. Lemak Abdominal Salah satu tempat penyimpanan lemak adalah rongga perut yang merupakan jaringan adiposa. Lemak merupakan salah satu penyusun jaringan untuk menyimpan energi oleh tubuh. Lemak diambil dari peredaran darah dan disimpan terutama di bawah kulit dan dalam perut secara bertahap (Piliang dan Djojosoebagjo, 1990). Deposit lemak ayam broiler umumya disimpan dalam bentuk lemak rongga tubuh di bawah kulit. Lemak rongga tubuh terdiri atas lemak abdominal, lemak rongga dada, dan lemak pada alat pencernaan. Persentase lemak abdominal pada ayam jantan berkisar antara 1,4%–2,6 % sedangkan untuk ayam betina antara 3,2%–4,8 % dari bobot hidup (Leeson dan Summers, 2000). Hal ini sesuai dengan pernyataan Becker et al. (1981) yang menyatakan bahwa persentase lemak abdominal pada ayam betina lebih tinggi dibandingkan ayam jantan. Penelitian Lubis et al. (2007) yang memberikan onggok fermentasi memperoleh lemak abdominal 11,10-17,27 gram atau 0,80%-1,13% dari bobot hidup. Penelitian yang dilakukan Bell dan Weaver (2002) menunjukkan adanya perbedaan lemak abdominal disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan. Ayam broiler yang dipelihara hingga umur 42 hari memiliki lemak abdominal 2,09%4,32% dari bobot hidup untuk ayam betina sedangkan pada ayam jantan 1,11%2,66% dari bobot hidup. Fontana et al. (1993) menyatakan lemak abdominal akan meningkat pada ayam yang diberi ransum dengan protein rendah dan energi ransum yang tinggi. Energi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak jaringan–jaringan. Bell dan Weaver (2002) menyatakan lemak abdominal ayam bisa meningkat jika diberikan ransum dengan tingkat lemak yang tinggi. Sebaliknya persentase lemak abdominal dapat diturunkan dengan meningkatkan kandungan serat kasar dalam ransumnya. 4 Organ Dalam Unggas memiliki organ pencernaan yang sederhana. Makanan utamanya berupa pakan dari biji-bijian, ikan, cacing, dan rumput-rumputan. Organ dalam yang berkembang pada unggas adalah perut, lidah, dan rempela karena tidak mempunyai gigi dan tulang rahang yang besar serta berotot. Hal tersebut menyebabkan sistem pencernaan unggas berkembang sesuai dengan makanan utamanya. Organ pencernaan unggas dimulai dari mulut, esofagus, rempela, usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ dalam tambahan sangat erat hubungannya dengan pencernaan karena sekresi yang dikeluarkan akan dialirkan ke dalam saluran usus untuk membantu pengolahan ransum. Organ–organ tersebut yaitu pankreas, hati, saluran empedu, serta organ vital lain seperti jantung dan limpa (Amrullah, 2004). Hati Hati ayam terdiri atas dua lobi (gelambir) yaitu kanan dan kiri, berwarna coklat tua, dan terletak diantara usus dan aliran darah. Bagian ujung hati yang normal berbentuk lancip, akan tetapi bila terjadi pembesaran dapat menjadi bulat (Mc Lelland, 1990). Secara umum fungsi hati meliputi pertukaran zat dari protein, lemak, dan karbohidrat, sekresi empedu, detoksifikasi senyawa beracun, dan ekskresi senyawa metabolit yang tidak berguna lagi bagi tubuh (Subronto, 1985). Salah satu peranan terpenting dari hati dalam pencernaan adalah menghasilkan cairan empedu yang disalurkan ke dalam duodenum melalui dua buah saluran. Cairan tersebut tersimpan di dalam kantung empedu yang terletak di lobus kanan hati (Akoso, 1993). Jaringan hati memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi sehingga gejala-gejala klinis gangguan jaringan tidak selalu dapat diamati (Subronto, 1985). Kelainan pada hati secara fisik biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna hati, pembengkakan, pengecilan pada salah satu lobi atau tidak adanya kantong empedu (Ressang, 1984). Persentase hati ayam berkisar antara 1,7%–2,8% dari bobot hidup (Putnam, 1991). Penelitian yang dilakukan Lubis et al. (2007) dengan memberikan 15% onggok fermentasi memperoleh bobot hati 32,58-35,57 gram atau sebesar 2,04%2,56% dari bobot hidup. Mc Lelland (1990) menyatakan warna hati tergantung pada status nutrisi unggas, hati yang normal berwarna coklat kemerahan atau coklat terang dan apabila makannnya berlemak tinggi, maka warnanya menjadi kuning. 5 Jantung Jantung merupakan organ yang memegang peranan penting di dalam peredaran darah dan mempunyai empat ruangan yaitu dua atrium dan dua ventrikel. Laju jantung dipengaruhi oleh ukuran tubuh, umur, dan temperatur lingkungan. Unggas yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil mempunyai laju pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan unggas yang mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar (Bell dan Weaver, 2002). Jantung sangat rentan terhadap racun dan zat antinutrisi, pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot jantung (Frandson, 1992). Jantung berfungsi sebagai pompa dan motor penggerak dalam peredaran darah serta bekerja secara otonom yaitu dikendalikan oleh sistem syaraf pusat diluar kemauan dan kesadaran manusia. Besar jantung tergantung pada jenis kelamin, umur, bobot badan, dan aktivitas hewan. Pembesaran ukuran jantung biasanya disebabkan adanya penambahan jaringan otot pada jantung. Dinding jantung mengalami penebalan, sedangkan ventrikel relatif menyempit apabila otot menyesuaikan diri pada kontraksi yang berlebihan (Ressang, 1984). Putnam (1991) menyatakan bahwa persentase jantung ayam broiler berkisar antara 0,42%–0,70% dari bobot hidup. Penelitian Lubis et al. (2007) yang menggunakan onggok fermentasi memperoleh bobot jantung 7,45-8,32 gram atau 0,49%-0,60% dari bobot hidup. Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial memperoleh bobot jantung ayam broiler 6,43-8,73 gram atau 0,50%-0,57% dari bobot hidup. Ginjal Ginjal pada unggas terletak di belakang paru–paru dan berjumlah dua buah. Saluran ureter menghubungkan antara ginjal dengan kloaka (Bell dan Weaver, 2002). Ginjal berperan dalam mempertahankan keseimbangan susunan darah dengan mengeluarakan zat–zat seperti air yang berlebih, sisa metabolisme, garam-garam organik, dan bahan–bahan lain yang terlarut dalam darah (Ressang, 1984). Ginjal merupakan organ yang menyaring plasma dari darah dan secara selektif menyerap kembali air serta unsur–unsur berguna dari filtrat, yang pada akhirnya mengeluarkan kelebihan dan produk buangan plasma. Hampir semua jenis ternak ginjalnya berbentuk seperti kacang (Frandson, 1992). Suprijatna et al. (2008) 6 menyatakan fungsi utama ginjal adalah memproduksi urin melalui pertama filtrasi darah sehingga air dan limbah metabolisme diekskresikan. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu reabsorpsi beberapa nutrien (misalnya glukosa dan elektrolit) yang kemungkinan digunakan kembali oleh tubuh. Penelitian Noormasari (2000) pada ayam broiler yang berumur 42 hari dengan pemberian onggok fermentasi memiliki bobot ginjal 3,33-4,18 gram atau 0,22%-0,29% dari bobot hidup. Pankreas Pankreas adalah organ yang berwarna merah terletak antara lipatan duodenal loop yang berfungsi dalam mensekresikan enzim amilase, protease, dan lipase untuk membantu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Bobot pankreas berkisar antara 2,5–4 gram pada ayam dewasa (Sturkie, 2000). Suprijatna et al. (2008) menyatakan pankreas adalah sebuah kelenjar yang menskresikan sari makanan yang kemudian masuk kedalam duodenum pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ pencernaan yang berada di tengah putaran duodenum yang berbentuk U dan berperan dalam sekresi enzim pencernaan (eksokrin) dan sekresi hormon (endokrin). Sebagai kelenjar endokrin, pankreas mensekresikan hormon insulin dan glikagon. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas mensekresikan cairan yang diperlukan bagi proses pencernaan di dalam usus halus, yaitu pancreatic juice. Cairan ini selanjutnya mengalir ke dalam duodenum melalui pancreatic duct (saluran pankreas) yang terdapat enzim-enzim untuk membantu pencernaan pati, lemak, dan protein. Beberapa enzim dari pankreas disimpan dan disekresikan dalam bentuk inaktif, dan menjadi aktif pada saat berada di saluran pencernaan (Suprijatna et al., 2008). Penelitian yang dilakukan Dewi (2007) dengan menggunakan ransum komersial memperoleh bobot pankreas 3,41-4,49 gram atau 0,24%-0,32% dari bobot hidup. Limpa Limpa berwarna merah gelap terletak di sebelah kanan abdomen yang merupakan perhubungan antara proventrikulus dengan rempela (Mc Lelland, 1990). Limpa berfungsi untuk menyimpan darah yang tidak ikut dalam peredaran darah, pada hewan muda berfungsi membentuk eritrosit bersama sumsum tulang, menghancurkan eritrosit tua, menyaring kuman dari darah, dan membentuk leukosit. Adanya benda asing dalam limpa menimbulkan proses reaktif yang secara 7 makroskopik mengakibatkan limpa membengkak. Ransum yang mengandung zat racun, anti nutrisi, dan penyakit menyebabkan limpa melakukan pembentukan sel limfosit untuk membentuk zat antibodi. Aktivitas limpa ini mengakibatkan limpa semakin membesar (Ressang, 1984). Putnam (1991) menyatakan bahwa bobot limpa ayam broiler berkisar antara 0,18%-0,23% dari bobot hidup. Penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial pada ayam broiler memperoleh bobot limpa 1,35-1,86 gram atau 0,11%0,12% dari bobot hidup. Penelitian yang dilakukan Lubis et al. (2007) dengan pemberian onggok fermentasi hingga taraf 15% memperoleh bobot limpa 2,90-3,41 gram atau 0,19%-0,25% dari bobot hidup. Rempela Rempela terletak diantara proventrikulus dengan batas atas usus halus, mempunyai dua pasang otot yang kuat dan sebuah mukosa. Kontraksi otot rempela baru akan terjadi apabila makanan masuk ke dalam. Rempela berisi bahan–bahan yang mudah terkikis seperti pasir, karang, dan kerikil. Partikel makanan yang berukuran besar akan dipecah menjadi partikel–partikel yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam saluran pencernaan (Bell dan Weaver, 2002). Kerja penggilingan dalam rempela terjadi secara tidak sadar oleh otot rempela yang memiliki kecenderungan untuk menghancurkan ransum seperti yang dilakukan oleh gigi (Blakely dan Bade, 1991). Grit yang ada dalam rempela mempunyai peranan yang penting untuk mengoptimalkan pencernaan karena dapat meningkatkan motilitas dan aktivitas menggiling dari rempela serta meningkatkan kecernaan pakan berupa biji–bijian hingga 10% (Sturkie, 2000). Penelitian Lubis et al. (2007) dengan menggunakan ayam berumur 42 hari memperoleh bobot rempela 30,77-35,28 gram atau 2,14%-2,23% dari bobot hidup. Putnam (1991) menyatakan bahwa persentase rempela adalah 1,6%–2,3 % dari bobot hidup. Usus Halus Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Terdapat berbagai enzim dalam usus halus yang berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan pemecahan karbohidrat, protein, serta lemak untuk mempermudah proses absorpsi (Suprijatna et al., 2008). Usus halus 8 terdiri atas duodenum (bagian depan), jejunum (bagian tengah), dan berakhir di ileum (bagian belakang). Usus halus merupakan tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan zat–zat makanan. Usus halus berfungsi sebagai penggerak aliran ransum dalam usus dan meningkatkan penyerapan zat makanan. Kemampuan ini ditunjang oleh adanya selaput lendir yang dilengkapi dengan jonjot usus yang lembut dan menonjol sehingga penyerapan zat makanan bisa maksimal. Perkembangan usus halus dipengaruhi oleh kandungan serat kasar dalam ransum (Akoso, 1993). Dalam usus halus disekresikan cairan-cairan yang mengandung enzim dan berperan penting dalam proses pencernaan. Kelenjar Brunner terdapat di daerah usus 12 jari yang menghasilkan cairan bersifat basa dan kaya dengan kandungan mukus. Respon usus 12 jari dalam proses sekresi cairannya akibat berhubungan dengan ransum yang dikonsumsi sebagian besar diatur oleh syaraf dan hormon (Piliang dan Djojosoebagjo, 1990). Ayam dewasa memiliki usus halus sepanjang 1,5 m. Bagian duodenum bermula dari ujung distal rempela. Bagian ini berbentuk kelokan yang biasa disebut duodenal loop. Pankreas menempel pada kelokan ini yang berfungsi mensekresiakan pancreatic juice yang mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Jejunum dan ileum merupakan segmen yang sulit dibedakan pada saluran pencernaan ayam. Beberapa ahli menyebut kedua segmen ini sebagai usus halus bagian bawah (Suprijatna et al., 2008). Aliran ransum dalam sistem pencernaan unggas sangat cepat. Berbeda dengan hewan ruminansia yang memiliki kemampuan untuk mencerna selulosa. Hal tersebut disebabkan sedikitnya bakteri dalam saluran pencernaan unggas sehingga ransum berserat hanya sedikit yang dapat dicerna (Blakely dan Bade, 1991). Ressang (1984) menyatakan pemanjangan usus dapat disebabkan radang usus. Radang usus ditandai dengan menurunnya nafsu makan dan kondisi tubuh yang memburuk. Rasa nyeri pada radang mengakibatkan rangsangan atas ujung-ujung syaraf sensoris yang selanjutnya akan meningkatkan frekuensi dan intensitas peristaltik usus. Peningkatan intensitas peristaltik usus akan meningkatkan panjang usus. Penelitian yang dilakukan Dewi (2007) dengan memberikan berbagai ransum komersial pada ayam hingga berumur 42 hari memperoleh panjang relatif duodenum 1,88-2,69 cm/kg, jejunum 4,30-6,42 cm/kg, dan ileum 4,60-6,69 cm/kg. 9 Usus Buntu (Seka) Unggas memiliki sepasang usus buntu (seka) yang terletak di perbatasan antara usus halus dan usus besar. Panjang masing–masing usus buntu sekitar 15 cm dan biasanya berisi makanan yang tidak tercerna dan akan dibuang (Bell dan Weaver, 2002). Usus buntu berfungsi dalam membantu penyerapan air serta mencerna karbohidrat dan protein dengan bantuan bakteri yang ada dalam usus buntu. Sebagian kecil serat dapat dicerna di dalam usus buntu yang disebabkan adanya bakteri fermentasi, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sebagian spesies mamalia (Pond et al., 1995). Menurut Grist (2006) isi seka akan kosong setiap delapan jam sekali. Seka akan menyerap kembali air dari isi usus, memecah selulosa dengan bantuan mikroba, sintesa vitamin, dan sekresi hormon. Unggas dewasa yang sehat memiliki seka yang berisi ransum lembut yang keluar masuk. Tidak ditemukan bukti mengenai peran seka serta dalam sistem pencernaan. Hanya sedikit air diserap, karbohidrat, dan protein yang dicerna berkat bantuan beberapa bakteri (Amrullah, 2004). Penelitian Dewi (2007) yang menggunakan berbagai ransum komersial memperoleh panjang relatif usus buntu 0,93-1,53 cm/kg. Usus Besar Usus besar terdiri atas sekum yang merupakan suatu kantung buntu dan kolon yang terdiri atas bagian yang naik, mendatar, dan turun. Bagian yang turun akan berakhir di rektum dan anus. Variasi pada usus besar (terutama pada bagian kolon yang naik) dari satu spesies ke spesies lain, jauh lebih menonjol dibandingkan dengan pada usus halus (Frandson, 1992). Usus besar merupakan tempat penyerapan kembali air dari usus halus. Usus besar berfungsi sebagai penyalur makanan dari usus kecil menuju kloaka untuk dibuang (Grist, 2006). Air asal urin diserap kembali di usus besar untuk ikut mengatur kandungan air sel–sel tubuh dan keseimbangan air. Panjang usus besar yang dimiliki ayam dewasa berkisar 8–10 cm/ekor. Ransum yang banyak mengandung serat dan bahan lain yang tidak dicerna seperti bebatuan kecil menimbulkan perubahan ukuran bagian-bagian saluran pencernaaan sehingga menjadi lebih berat, panjang, dan tebal (Amrullah, 2004). Blakely dan Bade (1991) menyatakan usus besar merupakan kelanjutan saluran pencernaan dari persimpangan usus buntu ke kloaka. 10 Onggok – Urea – Zeolit Fermentasi Onggok merupakan sumber energi dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 95,85%. Kandungan protein onggok masih sangat rendah, namun serat kasarnya cukup tinggi (Tabel 1). Salah satu teknologi alternatif untuk memanfaatkan onggok sebagai bahan baku pakan ternak adalah dengan mengubahnya menjadi produk yang berkualitas, yaitu melalui proses fermentasi (Phong et al., 2003). Beberapa penelitian melaporkan bahwa diantara mikroorganisme- mikroorganisme yang ada, Aspergillus niger sangat baik dalam menggunakan onggok sebagai substrat dan sekaligus meningkatkan kualitasnya (Lubis et al., 2007). Aspergillus niger dapat menggunakan berbagai macam zat makanan dari yang sederhana hingga komplek, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan memeliharanya. Proses fermentasi membutuhkan nitrogen dan mineral yang lebih tinggi untuk pertumbuhan dan reproduksi. Kapang Aspergillus niger bersifat aerobik, sehingga dalam pertumbuhannya memerlukan oksigen dalam jumlah yang banyak (Frazier dan Weshoff, 1981). Lehninger (1991) menyatakan kapang Aspergillus niger menghasilkan enzim urease untuk memecah urea menjadi asam amonia dan karbondioksida yang selanjutnya digunakan untuk pembentukan asam amino. Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Onggok dari Beberapa Sumber Berdasarkan Bahan Kering Komposisi Zat Gizi 1 2 3 Abu (%) 1,44 0,83 0,85 Protein kasar (%) 1,15 2,04 2,21 15,46 9,28 11,16 Lemak (%) 0,26 0,36 0,21 BETN (%) 82,09 87,49 85,45 Energi bruto (kkal/kg) 3.427 3.426 3.558 Serat kasar (%) Sumber: 1. Taram (1995) 2. Suhartono (2000) 3. Lubis et al.(2007) 11 Garraway dan Evans (1984) menyatakan urea yang terdapat dalam proses fermentasi akan diurai menjadi amonia dan karbodioksida. Amonia yang dihasilkan akan digunakan oleh mikroorganisme untuk membentuk asam amino. Nitrogen dalam media fermentasi mempunyai fungsi fisiologis bagi mikroorganisme, yaitu sebagai bahan untuk mensintesis protein, asam nukleat, dan koenzim. Lubis et al. (2007) melaporkan bahwa onggok-urea-zeolit yang difermentasi dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan protein kasar dari 2% menjadi 14%. Hasil tersebut jauh lebih tinggi dari hasil penelitian Iyayi dan Losel (2001) yang meningkatkan protein kasar onggok dari 3,6% menjadi 7,8% setelah difermentasi dengan Aspergillus niger. Zeolit merupakan sumber mineral yang murah sekaligus sebagai reservoir untuk amonia dalam proses fermentasi. Belum optimalnya konsentrasi protein kasar dalam penelitian tersebut diduga karena adanya komponen yang sangat diperlukan dalam membentukkan asam amino bersulfur tidak tersedia (Lubis et al., 2007). Penambahan sulfur diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi protein dalam fermentasi. Anwar et al. (1985) menyatakan bahwa struktur zeolit yang berpori dengan cairan di dalamnya yang mudah lepas, membuat zeolit mempunyai sifat spesial yaitu mampu menyerap senyawa, menyaring ukuran halus, menukar ion dan sebagai katalisator. Phong et al. (2003) melaporkan bahwa penambahan sulfur dalam bentuk amonium sulfat sebanyak 1,5% dapat meningkatkan protein dari 4,6% menjadi 9,4% dengan menggunakan Aspergillus niger. 12 MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (analisa ransum) dan Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Unggas, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (pemeliharaan, pemanenan, dan pengamatan ayam broiler), Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan bulan Juli hingga September 2009. Materi Ternak Penelitian ini menggunakan 200 ekor DOC strain Ross dengan merk dagang Jumbo 747 yang diperoleh dari perusahaan pembibitan PT. Cibadak Indah Sari Farm, Jakarta. Ayam dipelihara selama 35 hari dan pada periode akhir pemeliharaan diambil sampel sebanyak 40 ekor untuk pengamatan karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler. Kandang Kandang yang digunakan adalah kandang berbentuk petak yang terbuat dari bambu berukuran 1,2 x 1,2 x 2,5 meter sebanyak 24 buah. Kandang yang dipakai menggunakan sistem litter dengan alas sekam padi, masing-masing kandang berisi sepuluh ekor ayam. Setiap kandang dilengkapi dengan satu lampu 25 watt sebagai pemanas (brooder) dan penerangan. Peralatan Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan adalah tempat ransum bermerk Medion (nampan), tempat minum Medion berkapasitas tiga liter, tirai plastik penutup kandang, kertas koran, lampu 25 watt bermerk Eterna, gayung, ember, alat vaksin, alat desinfektan, gelas ukur, termometer, bambu untuk penyekat kandang, timbangan untuk menimbang ransum, dan alat tulis. Peralatan yang digunakan untuk evaluasi karkas, lemak abdominal, dan organ dalam ayam broiler adalah kertas label, pisau, cutter, pinset, gunting, timbangan digital bermerk Scout Pro Ohaus 4000 gram 12 volt 0,5 A dengan tingkat ketelitian 0,1 gram, timbangan digital bermerk AND HL 100 berkapasitas 100 x 0,01 gram, penggaris, meteran, panci, eviscerator, nampan, alas plastik, sarung tangan, masker, dan alat tulis. Ransum Ransum yang diberikan berasal dari PT Indofeed terdiri atas campuran jagung, dedak padi, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak kelapa, CaCO3, DCP, DL Methionin, campuran mineral, dan cassabio. Ransum perlakuan menggunakan cassabio dengan taraf 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Ransum perlakuan terdiri atas ransum periode starter yang diberikan pada saat ayam broiler berumur 7-14 hari dan ransum ayam periode finisher yang diberikan saat ayam broiler berumur 15-35 hari. Tabel 2. Komposisi Bahan dan Kandungan Gizi Ransum Penelitian Ransum Perlakuan Bahan Periode Starter C0 C10 C20 C30 Periode Finisher C40 C0 C10 C20 C30 C40 Jagung Kuning (%) 34,99 30,00 27,95 23,65 17,52 42,99 38,07 33,30 28,54 22,78 Dedak Padi (%) 23,71 20,30 11,55 20,00 15,60 11,11 Bungkil Kedelai (%) 25,60 24,00 24,80 25,50 24,95 Tepung Ikan (%) 10,00 10,00 10,00 6,15 2,83 6,61 2,78 24,00 22,72 21,02 19,32 19,74 9,00 9,00 7,31 7,91 8,87 9,83 9,00 Minyak Kelapa (%) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 CaCO3 (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DCP (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 DL Metehionin (%) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Campuran Mineral (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Cassabio (%) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 Kandungan Gizi BK (%) 84,48 83,71 85,30 86,80 89,31 88,93 88,14 87,74 88,82 87,44 Abu (%) 10,12 11,55 15,00 12,83 15,32 8,62 11,10 12,04 11,83 13,08 PK (%) 17,92 21,16 20,54 19,62 24,61 18,82 20,97 20,52 19,57 18,40 SK (%) 3,01 2,33 4,71 5,93 10,44 4,44 2,83 4,66 8,05 7,72 LK (%) 3,54 2,72 2,98 2,94 4,48 2,93 2,63 2,63 2,08 Beta-N (%) 49,89 45,95 42,07 45,48 35,57 52,57 50,31 47,89 46,74 46,16 EB (kkal/kg) 3.869 2.345 2.156 2.323 2.503 2.822 3.879 2.953 2.790 3.159 3,37 Keterangan : C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, C40 : cassabio 40%. 14 Tabel 3. Hasil Analisa Kandungan Zat Makanan Onggok dan Cassabio Berdasarkan Persentase Bahan Kering* Abu (%) PK (%) SK (%) LK (%) BETN (%) Onggok 30,80 3,92 12,37 0,16 52,74 Cassabio 20,74 ± 3,96 12,35 ± 1,70 16,08 ± 0,71 0,21 ± 0,01 50,62 ± 1,96 Keterangan : * Hasil analisa Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2009). PK : Protein kasar, SK : Serat kasar, LK : Lemak kasar, BETN : Bahan ekstrak tanpa nitrogen. Vaksin dan Obat-obatan Pencegahan penyakit ND (Newcastle Disease) atau tetelo dilakukan dengan vaksinasi sebanyak dua kali yaitu saat ayam berumur 3 hari (DOC) melalui tetes mata dan umur 28 hari melalui injeksi subkutan. Vitamin anti stress (Vitastress) untuk mencegah stress dilarutkan dalam air minum dan diberikan setiap hari selama minggu pertama dan dua hari sebelum serta sesudah vaksinasi. Rancangan Percobaan Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima taraf perlakuan dan empat ulangan (dalam satu ulangan diambil dua sampel ayam broiler). Taraf perlakuan yang diberikan adalah C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, dan C40 : cassabio 40%. Kadar cassabio yang digunakan pada ransum penelitian dihitung secara isoprotein dan isokalori. Yij = + i + ij Keterangan: Yij : Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. : Nilai tengah umum hasil pengamatan. I : Pengaruh perlakuan ke-i : i = 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. ijn : Pengaruh galat percobaan pemberian ransum perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam (Analysis of Varience/ ANOVA) dan jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Tukey (Gaspersz, 1991). 15 Peubah yang Diamati Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah : 1. Bobot hidup akhir (gram/ekor), diperoleh dari penimbangan bobot badan ayam (g) umur 35 hari sebelum dipotong. 2. Persentase karkas (%), diperoleh dari perbandingan bobot karkas ayam (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. 3. Persentase lemak abdominal (%), diperoleh dari perbandingan lemak abdominal (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. 4. Organ dalam ayam a. Persentase hati (%), diperoleh dari perbandingan bobot hati (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. b. Persentase jantung (%), diperoleh dari perbandingan bobot jantung (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. c. Persentase ginjal (%), diperoleh dari perbandingan bobot ginjal (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. d. Persentase pankreas (%), diperoleh dari perbandingan bobot pankreas (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. e. Persentase limpa (%), diperoleh dari perbandingan bobot limpa (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. 5. Saluran pencernaan a. Persentase rempela (%), diperoleh dari perbandingan bobot rempela (g) dengan bobot hidup akhir ayam (g) dikalikan 100%. b. Panjang relatif duodenum (cm/kg), diperoleh dari perbandingan panjang duodenum (cm) dengan bobot hidup (kg). c. Panjang relatif jejunum (cm/kg), diperoleh dari perbandingan panjang jejunum dengan bobot hidup (kg). d. Panjang relatif ileum (cm/kg), diperoleh dari perbandingan panjang ileum (cm) dengan bobot hidup (kg). e. Panjang relatif seka (cm/kg), diperoleh dari perbandingan panjang seka (cm) dengan bobot hidup (kg). f. Panjang relatif usus besar (cm/kg), diperoleh dari perbandingan panjang usus besar (cm) dengan bobot hidup (kg). 16 Prosedur Pembuatan Cassabio Pembuatan cassabio dimulai dari onggok dicampurkan dengan zeolit sebanyak 2,5% dari BK onggok, lalu dipanaskan menggunakan autoclave dengan suhu 1200C dan tekanan 250 psi selama 15 menit. Campuran tersebut lalu difermentasi dengan ditambahkan urea sebanyak 3%, amonium sulfat 1,5%, Aspergillus niger 0,2% dari BK onggok, dan aquades. Proses fermentasi dilakukan selama 6 hari, setelah itu cassabio dijemur selama 3 hari di bawah sinar matahari agar Aspergillus niger inaktif. Cassabio yang telah kering lalu digiling dan dicampur ransum sesuai dengan masing-masing taraf perlakuan. Alur proses pembuatan cassabio dapat dilihat pada Gambar 1. Onggok Autoclave Onggok dan zeolit Urea 3% Zeolit Fermentasi 6 hari Amonium Sulfat 1,5% Aspergillus niger 0,2 % Cassabio Aquades Gambar 1. Alur Proses Pembuatan Cassabio 17 Persiapan Kandang Kandang dibersihkan dengan disapu, disikat, dicuci, dan disterilisasai menggunakan desinfektan satu minggu sebelum pemeliharaan. Setelah itu, dilakukan pegapuran pada dinding dan lantai kandang untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan ayam broiler. Tempat ransum dan air minum disiapkan dan dibersihkan. Kandang lalu diberi sekam padi sebagai alas. Setiap kandang terdapat satu tempat ransum, satu tempat minum, dan satu buah lampu 25 watt yang dipasang di tengah-tengah kandang (sekitar 20-30 cm di atas kepala ayam). Sekeliling kandang ditutup dengan menggunakan tirai plastik sebagai pelindung untuk mengurangi pengaruh lingkungan. Pemeliharaan Masing-masing kandang diberi nomor perlakuan C0, C10, C20, C30, dan C40. Pemberian ransum dilakukan dua kali sehari yaitu pukul 07.00 dan 16.00 WIB. Jumlah pemberian ransum bertambah disesuaikan dengan kebutuhan ayam broiler. Air minum diberikan ad libitum (tidak terbatas). Pencegahan penyakit dilakukan dengan pemberian vaksin ND dan vaksin gumboro. Pencegahan stress pada ayam dengan diberikan vitachick dan vitastress. Ayam broiler yang telah berumur 35 hari dipanen dan diamati. Pemanenan dan Pengamatan Ayam Broiler Pemanenan dilakukan pada hari ke-35, sebanyak 40 ekor ayam dipuasakan selama ±12 jam pada hari sebelumnya untuk mengosongkan isi organ dalam sehingga mempermudah pengamatan. Ayam broiler lalu ditimbang bobot hidupnya kemudian dipotong dengan posisi kepala di bawah. Pemotongan ayam dilakukan menggunakan metode kosher style pada bagian antara tulang kepala dengan tulang atlas. Bagian yang dipotong terdiri atas empat saluran yaitu pembuluh darah vena jugularis, arteri karotidae, esofagus, dan trakea. Ayam yang telah dipotong didiamkan selama ±2 menit agar darah keluar sempurna. Ayam yang sudah dipotong, kemudian dicelup dalam air panas (scalding) selama ±1 menit untuk mempermudah proses pembuluan. Ayam lalu dibului (defeathering) dan diambil organ dalamnya (evisceration) serta dipisahkan antara bagian kepala, leher, dan ceker. Karkas ayam, lemak abdominal, hati, jantung, 18 pankreas, limpa, ginjal, dan rempela yang sudah dipisahkan lalu dibersihkan, ditimbang, dan diamati. Pengukuran panjang usus halus (duodenum, jejunum, dan ileum), seka, dan usus besar diukur dengan meteran. Alur proses pemanenan dan pengamatan ayam broiler dapat dilihat pada Gambar 2. Pemanenan Pemisahan Organ Dalam Penimbangan Organ Dalam Penimbangan Bobot Hidup Pembuluan Penimbangan Karkas Pemotongan Ayam Pencelupan di Air Panas Pengukuran Saluran Pencernaan Gambar 2. Alur Proses Pemanenan dan Pengamatan Ayam Broiler 19 HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler Ayam broiler penelitian yang telah dipelihara dipuasakan selama 12 jam sebelum dipotong untuk mempermudah proses evaluasi akhir. Hari ke 35 ayam broiler dipotong dan dievaluasi meliputi bobot hidup akhir, karkas, dan lemak abominal. Data rataan parameter peubah yang diamati dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Evaluasi Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler Perlakuan Peubah C0 C10 C20 C30 C40 1.597,50 ± 152,57 1.595,00 ± 148,81 1.565,00 ± 138,15 1.457,50 ± 141,19 1.385,00 ± 238,09 Karkas (%) 63,33 ± 3,38 62,88 ± 5,56 61,65 ± 4,31 63,82 ± 6,01 61,87 ± 3,60 Lemak Abdominal (%) 2,04 ± 0,36a 1,74 ± 0,82 ab 1,31 ± 0,27 b 1,52 ± 0,27 ab 1,33 ± 0,54 ab Bobot Hidup Akhir (g/ekor) Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05); C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, C40 : cassabio 40%. Bobot Hidup Akhir Bobot badan ayam broiler dapat dipengaruhi oleh kualitas ransum yang diberikan. Semakin baik ransum yang diberikan pada ayam maka akan menghasilkan bobot hidup yang tinggi. Hasil analisis ragam menunjukan pemberian cassabio hingga taraf 40% tidak berpengaruh terhadap bobot hidup akhir ayam broiler (Tabel 4). Rataan bobot hidup akhir ayam broiler berkisar antara 1.385-1.597,50 gram/ekor. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Noormasari (2000) yang menggunakan onggok fermentasi hingga taraf 15% dengan memperoleh bobot hidup akhir ayam broiler 1.380-1.596,67 gram/ekor dan penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial dengan memperoleh bobot hidup akhir 1.132-1.658 gram/ekor, sehingga dapat diketahui bobot hidup ayam broiler penelitian tergolong normal. Piliang dan Djojosoebagjo (1990) menyatakan kandungan serat kasar yang tinggi dapat mengurangi berat badan karena serat makanan akan tertinggal dalam saluran pencernaan dalam kurun waktu singkat, sehingga absorbsi zat makanan berkurang. Anggorodi (1985) menambahkan semakin tinggi kandungan serat kasar dalam suatu bahan makanan maka semakin rendah daya cerna makanan tersebut. Faktor–faktor yang mempengaruhi bobot hidup ayam broiler yaitu konsumsi ransum, kualitas ransum yang diberikan, jenis kelamin, lama pemeliharaan, dan aktivitas yang dilakukan ternak (Soeparno, 1994). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kebutuhan nutrisi ayam broiler pada umur yang berbeda. Ayam broiler yang telah mencapai periode finisher akan mengkonsumsi ransum yang lebih banyak dibandingkan ayam broiler pada periode starter. Ayam broiler akan terus mengkonsumsi ransum hingga kebutuhan nutrisi tubuhnya tercukupi. Persentase Karkas Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase karkas ayam broiler adalah persentase bobot hidup. Persentase karkas merupakan perbandingan bobot karkas dengan bobot hidup, sehingga bobot hidup yang besar akan diikuti pula oleh bobot karkas yang besar begitupun sebaliknya (Soeparno, 1994). Penambahan cassabio hingga taraf 40% pada ransum penelitian secara statistik tidak berpengaruh terhadap pesentase karkas ayam broiler (Tabel 4). Persentase karkas ayam broiler hasil penelitian antara 61,65%-63,82% dari bobot hidup. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Pesti dan Bakali (1997) yang memperoleh persentase karkas ayam broiler berkisar antara 60,52%-69,91% dari bobot hidup dan penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial memperoleh 63,79%-67,78% dari bobot hidup. Persentase karkas ayam broiler pada penelitian ini masih lebih rendah dari penelitian yang dilakukan Lubis et al. (2007) dengan memberikan onggok fermentasi hingga taraf 15% yang memperoleh persentase karkas 68,89%-70,78%. Perbedaan tersebut dapat disebabkan umur ayam broiler pada penelitian ini hanya 35 hari sedangkan pada penelitian Lubis et al. (2007) berumur 42 hari. Terdapat hubungan linier antara protein, energi, dan persentase karkas ayam broiler. Protein dan energi yang terkandung dalam ransum, akan digunakan untuk memproduksi daging dalam tubuh ayam broiler (Pesti dan Bakali, 1997). Imbangan antara protein dan energi yang terkandung dalam ransum penelitian walaupun berbeda-beda namun tidak menurunkan persentase karkas, sehingga diduga bahwa imbangan protein dan energi dalam ransum cassabio masih sesuai untuk pembentukan karkas ayam broiler. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 21 cassabio pada ransum penelitian tidak menghambat pembentukan karkas ayam broiler. Wahju (2004) menyatakan tingginya bobot karkas ayam broiler ditunjang oleh bobot hidup akhir yang tinggi. Persentase karkas selain disebabkan oleh bobot hidup yang dihasilkan, dipengaruhi pula oleh penanganan dalam proses pemotongan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Murugesan et al. (2005) yang menyatakan penanganan yang dilakukan saat proses pemotongan dapat mempengaruhi produksi karkas. Faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan dan komposisi tubuh yang meliputi distribusi berat dan komponen karkas. Faktor nutrisi, umur, dan laju pertumbuhan dapat mempengaruhi komposisi bobot karkas dan persentase karkas yang biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya bobot hidup ayam. Penurunan biasanya terjadi pada persentase bagian non karkas (offal) seperti darah, usus halus, dan organ vital (Soeparno, 1994). Persentase Lemak Abdominal Deposit lemak ayam broiler umunya disimpan dalam bentuk lemak rongga tubuh di bawah kulit. Lemak rongga tubuh terdiri atas lemak abdominal, lemak rongga dada, dan lemak pada alat pencernaan (Leeson dan Summers, 2000). Penumpukan lemak terbanyak pada ayam broiler biasanya terdapat pada bagian abdominal. Berdasarkan hasil analisis ragam pada Tabel 4, memperlihatkan cassabio yang ditambahkan dalam ransum penelitian berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal. Hasil uji Tukey menunjukkan persentase lemak abdominal tertinggi yaitu perlakuan C0 sebesar 2,04% dan terendah yakni perlakuan C20 sebesar 1,31%. Nilai tersebut lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan Noormasari (2000) yang menggunakan onggok fermentasi bertaraf 15% dengan memperoleh persentase lemak abdominal 0,80%-1,13% dari bobot hidup dan penelitian Dewi (2007) yang menggunakan ransum komersial dengan memperoleh 0,85%-1,49% dari bobot hidup. Tingginya persentase lemak abdominal pada C0 dapat diakibatkan ransum yang diberikan (Tabel 3) mengandung lemak kasar yang mencapai 4,48% dan kandungan serat kasar 4,44% sedangkan pada C20 kadar lemak kasarnya 2,63% dan serat kasar 4,63%. Kandungan serat kasar yang rendah dan kadar lemak kasar yang lebih tinggi pada ransum C0 mengakibatkan deposit lemak menjadi lebih banyak 22 pada tubuh ayam terutama bagian abdominal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fontana et al. (1993) yang menyatakan lemak abdominal akan meningkat pada ayam yang diberi ransum dengan protein rendah, energi ransum yang tinggi, dan serat kasar yang rendah. Lemak abdominal ayam broiler dapat meningkat jika diberikan ransum dengan kandungan lemak yang tinggi. Persentase lemak abdominal dapat diturunkan dengan meningkatkan kandungan serat kasar dalam ransumnya. Ransum ternak ayam broiler perlu mengandung lemak dalam jumlah yang cukup karena dalam proses metabolisme lemak mempunyai energi 2,25 kali lebih besar dari karbohidrat (Bell dan Weaver, 2002). Semakin tinggi kadar lemak akan mempengaruhi kualitas karkas yang dihasilkan. Tingginya kadar lemak pada ayam broiler akan menurunkan harga jual karena karkas yang saat ini dikonsumsi masyarakat cenderung menghindari kadar lemak yang berlebih. Bell dan Weaver (2002) menyatakan bahwa penurunan rasio jumlah energi atau peningkatan persentase protein akan meningkatkan laju pertumbuhan dan akan meningkatkan jumlah lemak abdominal. Evaluasi Organ Dalam Ayam Broiler Ayam broiler penelitian dipuasakan satu hari sebelum dipotong untuk mengosongkan isi organ dalamnya sehingga mempermudah proses pengamatan. Evaluasi organ dalam ayam broiler yang dilakukan meliputi pengamatan hati, jantung, ginjal, pankreas, dan limpa. Data rataan organ dalam dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Evaluasi Organ Dalam Ayam Broiler Perlakuan Peubah C0 C10 C20 C30 C40 Hati (%) 2,89 ± 0,41 2,96 ± 0,45 2,72 ± 0,24 3,14 ± 0,37 2,66 ± 0,36 Jantung (%) 0,45 ± 0,06 0,43 ± 0,06 0,45 ± 0,07 0,45 ± 0,10 0,52 ± 0,18 Ginjal (%) 0,64 ± 0,15 0,78 ± 0,18 0,69 ± 0,13 0,74 ± 0,16 0,61 ± 0,09 Pankreas (%) 0,36 ± 0,13 0,29 ± 0,10 0,32 ± 0,07 0,32 ± 0,07 0,31 ± 0,09 Limpa (%) 0,10 ± 0,04 0,12 ± 0,04 0,09 ± 0,03 0,10 ± 0,04 0,09 ± 0,02 Keterangan : C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, C40 : cassabio 40%. 23 Persentase Hati Hati berkaitan erat dengan pertumbuhan pada ayam broiler. Ayam broiler yang memiliki hati normal akan tumbuh dengan baik. Hal tersebut disebabkan hati mempunyai fungsi yang kompleks yaitu berperan dalam metabolisme lemak, protein, karbohidrat, zat besi, detoksifikasi racun yang masuk ke dalam tubuh ayam broiler, pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyimpanan vitamin (Ressang, 1984). Cassabio yang ditambahkan dalam ransum penelitian hingga taraf 40% secara statistik tidak berpengaruh terhadap persentase hati (Tabel 5). Kisaran persentase hati penelitian adalah 2,66%-3,14% dari bobot hidup. Hasil tersebut lebih tinggi dari penelitian Noormasari (2000) dengan menggunakan ayam broiler berumur 42 hari yang memperoleh 2,04%-2,56% dan Putnam (1991) yang memperoleh persentase hati 1,70%–2,80% dari bobot hidup. Salah satu fungsi hati adalah detoksifikasi racun dan apabila terjadi kelainan ditunjukkan dengan adanya pembesaran atau pengecilan hati. Fungsi hati secara fisiologis yaitu sekresi empedu, detoksifikasi senyawa racun bagi tubuh, penyimpanan vitamin dan lemak, destruksi sel darah merah, pembentukan protein plasma, inaktifasi hormon polipeptida, metabolisme protein, karbohidrat, dan lipida (Ressang, 1984). Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Empedu penting dalam proses penyerapan lemak dan eskresi limbah produk (Suprijatna et al., 2008). Persentase Jantung Penambahan cassabio pada ransum penelitian berdasarkan analisis ragam tidak berpengaruh terhadap persentase jantung (Tabel 5). Persentase jantung ayam broiler hasil penelitian antara 0,43%-0,52% dari bobot hidup. Nilai tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Noormasari (2000) dengan menggunakan onggok fermentasi hingga taraf 15 % yang memperoleh 0,49%-0,60% dan penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial memperoleh persentase jantung 0,50%0,57% dari bobot hidup. Putnam (1991) menyatakan persentase jantung ayam broiler yang normal berkisar antara 0,42%–0,70% dari bobot hidup, sehingga dapat diketahui bahwa jantung ayam penelitian tergolong normal. Laju jantung dipengaruhi oleh ukuran tubuh, umur, dan temperatur lingkungan. Unggas yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil mempunyai laju 24 pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan unggas yang mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar (Bell dan Weaver, 2002). Jantung sangat rentan terhadap racun dan zat antinutrisi, pembesaran jantung dapat terjadi karena adanya akumulasi racun pada otot jantung (Frandson, 1992). Jantung berfungsi sebagai pompa dan motor penggerak dalam peredaran darah serta bekerja secara otonom yaitu dikendalikan oleh sistem syaraf pusat diluar kemauan dan kesadaran manusia. Besar jantung tergantung pada jenis kelamin, umur, bobot badan, dan aktivitas hewan. Pembesaran ukuran jantung biasanya disebabkan adanya penambahan jaringan otot pada jantung (Ressang, 1984). Persentase Ginjal Ginjal merupakan organ yang menyaring plasma dari darah dan secara selektif menyerap kembali air serta unsur–unsur berguna yang kembali dari filtrat, yang pada akhirnya mengeluarkan kelebihan dan produk buangan plasma (Frandson, 1992). Pemberian cassabio pada ransum hingga taraf 40%, tidak berpengaruh terhadap persentase ginjal ayam broiler secara statistik (Tabel 5). Persentase ginjal hasil penelitian berkisar antara 0,61%-0,78% dari bobot hidup. Persentase tersebut lebih tinggi dari penelitian Lubis et al. (2007) yang memberikan penambahan onggok fermentasi hingga taraf 15% dengan memperoleh persentase ginjal 0,22%0,29% dari bobot hidup. Ginjal berperan dalam mempertahankan kese-imbangan susunan darah dengan mengeluarkan zat–zat seperti air yang berlebih, garam organik, dan bahan lain yang terlarut dalam darah (Ressang, 1984). Suprijatna et al. (2008) menyatakan fungsi utama ginjal adalah memproduksi urin melalui filtrasi darah sehingga air dan limbah metabolisme diekskresikan. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu reabsorpsi beberapa nutrien (misalnya glukosa dan elektrolit) yang kemudian digunakan kembali oleh tubuh. Persentase Pankreas Hasil analisis ragam memperlihatkan cassabio yang digunakan dalam ransum penelitian tidak berpengaruh terhadap persentase pankreas (Tabel 5). Persentase pankreas hasil penelitian yaitu 0,29%-0,36% dari bobot hidup. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial dengan 25 memperoleh persentase pankreas sebesar 0,24%-0,32%. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas kerja pankreas masih dalam kondisi normal, sesuai pernyataan Ressang (1984) yang menyatakan pankreas yang bekerja secara normal akan mensekresikan enzim-enzim pencernaan ke dalam duodenum yang dapat membantu memecah serat kasar tinggi dengan bantuan enzim-enzimnya, sehingga mudah dicerna oleh ayam broiler. Pankreas berfungsi untuk mensekresi enzim amilase, protease, dan lipase yang membantu proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Berat pankreas berkisar antara 2,5–4 gram pada ayam dewasa (Sturkie, 2000). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Suprijatna et al. (2008) yang menyatakan pankreas adalah sebuah kelenjar yang menskresikan sari cairan yang diperlukan bagi proses pencernaan usus halus, yaitu pancreatic juice. Cairan ini selanjutnya mengalir ke dalam duodenum melalui saluran pankreas, dimana terdapat enzim yang membantu pencernaan pati, lemak, dan protein. Beberapa enzim dari pankreas disimpan dan disekresikan dalam bentuk inaktif dan menjadi aktif pada saat berada di saluran pencernaan. Enzim nuklease, lipase, dan amilase disekresikan dalam bentuk aktif. Persentase Limpa Limpa berfungsi untuk menyimpan darah yang tidak ikut dalam peredaran darah, membentuk sel darah merah bersama sumsum tulang, menghancurkan sel darah merah tua, menyaring kuman dari darah, dan membentuk sel darah putih (Ressang, 1984). Penambahan cassabio hingga taraf 40% berdasarkan analisis ragam tidak mempengaruhi persentase limpa (Tabel 5). Limpa hasil penelitian memiliki persentase antara 0,09%-0,12% dari bobot hidup. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Dewi (2007) yang memberikan ransum komersial dengan memperoleh persentase limpa 0,11%-0,12% dari bobot hidup. Persentase limpa hasil penelitian masih dibawah penelitian Lubis et al. (2007) yang memberikan onggok fermentasi bertaraf 15% dengan memperoleh persentase limpa 0,19%-0,25% dari bobot hidup. Lebih rendahnya persentase limpa ayam broiler hasil penelitian, dapat disebabkan umur pemeliharaan ayam broiler penelitian ini lebih muda 7 hari dari penelitian Lubis et al. (2007). Ressang (1984) berpendapat adanya benda asing dalam limpa menimbulkan proses reaktif yang secara makroskopik mengakibatkan limpa membengkak. Ransum 26 yang mengandung zat racun, anti nutrisi, dan penyakit menyebabkan limpa melakukan pembentukan sel limfosit untuk membentuk zat antibodi. Aktivitas limpa ini mengakibatkan limpa semakin membesar. Evaluasi Saluran Pencernaan Ayam Broiler Saluran pencernaan yang berkembang pada ayam broiler adalah perut, lidah, dan rempela karena tidak mempunyai gigi dan tulang rahang yang besar serta berotot. Pemuasaan ayam broiler satu hari sebelum proses evaluasi akhir untuk mempermudah proses pengamatan saluran pencernaan. Evaluasi akhir saluran pencernaan ayam broiler meliputi persentase rempela, panjang relatif duodenum, jejunum, ileum, usus buntu (seka), dan usus besar. Data rataan saluran pencernaan ayam broiler dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Evaluasi Saluran Pencernaan Ayam Broiler Perlakuan Peubah C0 C10 C20 C30 C40 Rempela (%) 1,20 ± 0,19 1,22 ± 0,24 1,08 ± 0,13 1,25 ± 0,20 1,17 ± 0,23 Panjang Relatif Duodenum (cm/kg) 1,92 ± 0,26 1,94 ± 0,43 1,99 ± 0,33 1,92 ± 0,47 2,36 ± 1,08 Panjang Relatif Jejunum (cm/kg) 5,05 ± 0,65 4,64 ± 1,29 5,33 ± 0,96 5,84 ± 0,56 5,18 ± 0,65 Panjang Relatif Ileum (cm/kg) 5,24 ± 0,66 5,36 ± 0,54 5,58 ± 1,59 6,67 ± 1,23 5,91 ± 0,77 Panjang Relatif Seka (cm/kg) 1,05 ± 0,14 1,15 ± 0,18 1,19 ± 0,24 1,31 ± 0,15 1,32 ± 0,27 Panjang Relatif Usus Besar (cm/kg) 0,46 ± 0,11a 0,50 ± 0,09a 0,56 ± 0,14ab 0,69 ± 0,13b 0,52 ± 0,14ab Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05); C0 : cassabio 0%, C10 : cassabio 10%, C20 : cassabio 20%, C30 : cassabio 30%, C40 : cassabio 40%. Persentase Rempela Rempela merupakan organ pencernaan yang berperan penting untuk proses penghancuran partikel-partikel makanan menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dicerna oleh ayam broiler. Penambahan cassabio dalam ransum penelitian secara statistik tidak berpengaruh terhadap persentase rempela ayam broiler (Tabel 6). 27 Persentase rempela hasil penelitian antara 1,08%-1,25% dari bobot hidup. Nilai tersebut masih dibawah penelitian Noormasari (2000) yang menggunakan onggok fermentasi bertaraf 15% dengan memperoleh persentase rempela 2,14%-2,23%, penelitian Putnam (1991) yang memperoleh persentase rempela 1,60%–2,30% dan penelitian Dewi (2007) dengan memberikan berbagai ransum komersial yang memperoleh persentase rempela 1,68%-2,09% dari bobot hidup. Lebih rendahnya persentase rempela ayam hasil penelitian ini dapat disebabkan ayam yang dievaluasi berumur 35 hari sedangkan penelitian yang lain berumur 42 hari. Rempela berisi bahan–bahan yang mudah terkikis seperti pasir, karang, dan kerikil. Partikel makanan yang berukuran besar akan segera dipecah menjadi partikel–partikel yang sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam saluran pencernaan (Bell dan Weaver, 2002). Partikel ransum yang lebih besar menyebabkan kontraksi semakin cepat. Grit yang ada dalam rempela mempunyai peranan yang penting untuk mengoptimalkan pencernaan karena dapat meningkatkan motilitas dan aktivitas menggiling dari rempela serta meningkatkan kecernaan pakan berupa biji–bijian hingga 10 % (Sturkie, 2000). Kerja penggilingan dalam rempela yang terjadi secara tidak sadar oleh otot rempela yang memiliki kecenderungan untuk menghancurkan ransum seperti yang dilakukan oleh gigi (Blakely dan Bade, 1991). Panjang Relatif Duodenum Usus halus berkaitan erat dengan pertumbuhan pada ayam broiler karena di tempat ini sari-sari makanan dari ransum yang dikonsumsi akan diserap oleh tubuh ayam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akoso (1993) yang menyatakan usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan, penyerapan zat–zat makanan, dan penggerak aliran ransum. Kemampuan ini ditunjang oleh adanya selaput lendir yang dilengkapi dengan jonjot usus yang lembut dan menonjol seperti jari (vili), sehingga penyerapan zat–zat makanan bisa maksimal yang bermanfaat untuk pertumbuhan ayam broiler. Ayam yang sehat akan memiliki bentuk dan ukuran usus halus yang normal. Duodenum berfungsi sebagai pusat terjadinya lipolisis dalam tubuh ayam broiler. Dinding duodenum akan mensekresikan enzim yang mampu meningkatkan ph zat makanan yang masuk dalam tubuh, sehingga kelarutan dan penyerapan di jejunum dan ileum akan meningkat (Anggorodi, 1985). Hasil analisis ragam 28 menunjukkan penambahan cassabio tidak mempengaruhi panjang relatif duodenum (Tabel 6). Panjang relatif duodenum hasil penelitian antara 1,92-2,36 cm/kg. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2007) dengan memberikan berbagai ransum komersial yang memperoleh 1,88-2,69 cm/kg. Usus halus terdiri atas beberapa bagian yang dimulai dari duodenum (bagian depan), jejunum (bagian tengah), dan berakhir di ileum (bagian belakang). Perkembangan usus halus dipengaruhi oleh kandungan serat kasar dalam ransum yang dikonsumsi oleh ayam broiler (Akoso, 1993). Segmen yang pertama, duodenum, bermula dari ujung distal rempela. Bagian ini berbentuk kelokan, disebut sebagai duodenal loop. Pankreas menempel pada kelokan ini. Sepanjang permukaan lumen usus halus terdapat banyak vili. Setiap vilus mengandung pembuluh limfe yang disebut lacteal dan pembuluh kapiler. Permukaan vili terdapat banyak mikrovili yang berfungsi melakukan absorpsi hasil pencernaan (Suprijatna et al., 2008). Panjang Relatif Jejunum Cassabio yang ditambahkan dalam ransum penelitian hingga taraf 40% tidak berpengaruh terhadap panjang relatif jejunum secara statistik. Panjang relatif jejunum hasil penelitian berkisar antara 4,64-5,84 cm/kg. Nilai tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2007) dengan memberikan ransum komersial yang memperoleh panjang relatif jejunum 4,30-6,42 cm/kg. Hal tersebut menunjukkan panjang relatif jejunum penelitian ini tergolong normal. Jejunum berperan sebagai tempat penyerapan zat makanan yang terbesar dalam tubuh ayam broiler. Jejenum dan ileum merupakan segmen yang sulit dibedakan pada saluran pencernaan ayam broiler, namun dapat dilihat dengan adanya divertikulum yang tampak di permukaan usus halus. Jejunum memanjang dari duodenum hingga ileum (Grist, 2006). Tidak seperti ruminansia yang memiliki kemampuan untuk mencerna selulosa, pada unggas aliran ransum dalam sistem pencernaan sangat cepat. Hal tersebut disebabkan sedikitnya bakteri dalam saluran pencernaan sehingga ransum berserat hanya sedikit yang dapat dicerna. Sebagian besar pencernaan terjadi dalam usus halus (Blakely dan Bade, 1991). 29 Panjang Relatif Ileum Ileum merupakan tempat pertumbuhan bakteri pada saluran pencernaan ayam broiler (Anggorodi, 1985). Penambahan cassabio berdasarkan analisis ragam, tidak berpengaruh terhadap panjang relatif ileum ayam broiler (Tabel 6). Panjang relatif ileum hasil penelitian berkisar 5,24-6,67 cm/kg. Hal tersebut sesuai penelitian Dewi (2007) dengan memberikan berbagai ransum komersial dari beberapa perusahaan komersial yang memperoleh panjang relatif ileum 4,60-6,69 cm/kg. Panjang usus halus dapat dipengaruhi jenis bahan baku yang diberikan pada ternak. Terdapat beberapa jenis serat yang sulit dicerna oleh unggas seperti selulosa, lignin, dan silika. Bila ransum mengandung ketiga serat tersebut maka dapat meningkatkan kerja usus dalam mencerna dan menyerap zat makanan yang ditunjukkan dengan semakin panjangnya ukuran usus halus (Amrullah, 2004). Grist (2006) menyatakan ileum memanjang dari divertikulum sampai persimpangan ileocaecal, dimana dua sekum bersatu dengan usus. Gerakan peristaltik (kontraksi otot polos) juga terjadi disini untuk mendorong bahan-bahan dalam sistem pencernaan ke seka dan rektum (Blakely dan Bade, 1991). Piliang dan Djojosoebagjo (1990) menyatakan dalam usus halus disekresikan cairan-cairan yang mengandung enzim dan berperan penting dalam proses pencernaan. Panjang Relatif Seka Penambahan cassabio hingga taraf 40 % dalam ransum penelitian secara statistik tidak berpengaruh terhadap panjang relatif seka (usus buntu) ayam broiler (Tabel 6). Hasil penelitian ini menunjukan panjang relatif seka berkisar antara 1,051,32 cm/kg. Nilai tersebut sesuai penelitian Dewi (2007) yang menggunakan ransum komersial pada ayam hingga berumur 42 hari dengan memperoleh 0,93-1,53 cm/kg. Bell dan Weaver (2002) menyatakan usus buntu biasanya berisi makanan yang tidak tercerna dan akan dibuang keluar tubuh. Unggas memiliki sepasang usus buntu yang berfungsi dalam membantu penyerapan air dan mencerna karbohidrat serta protein dengan bantuan bakteri yang ada dalam seka. Sebagian kecil serat dapat dicerna di dalam seka karena adanya bakteri fermentasi (Pond et al., 1995). Seka juga berfungsi memecah selulosa dengan bantuan mikroorganisme, mensintesa vitamin, dan sekresi hormon (Grist, 2006). Blakely dan Bade (1991) menyatakan seka pada ayam broiler dapat disamakan 30 dengan seka pada manusia, dengan fungsi yang tidak diketahui dengan pasti. Hanya sedikit saja pencernaan serat kasar yang terjadi disini. Unggas dewasa yang sehat memiliki seka yang berisi ransum yang lembut. Seka hanya menyerap sedikit air, karbohidrat, dan protein akibat dari adanya mikroba di dalamnya yang membutuhkan nutrien tersebut untuk tumbuh dan berkembang (Suprijatna et al., 2008). Panjang Relatif Usus Besar Usus besar tidak mensekresikan enzim, namun didalamnya terjadi proses penyerapan air untuk meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air ayam broiler (Bell dan Weaver, 2002). Hasil analisis ragam memperlihatkan penambahan cassabio dalam ransum penelitian berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap panjang relatif usus besar. Hasil uji Tukey memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada perlakuan C0, C10, dan C30. Panjang relatif C30 yaitu 0,69 cm/kg lebih panjang dari perlakuan C0 yaitu 0,46 cm/kg dan C10 yakni 0,50 cm/kg. Peningkatan panjang relatif usus besar diduga disebabkan oleh kadar serat kasar pada C0 dan C10 masing-masing 4,44% dsn 2,83% lebih rendah daripada kadar serat kasar C30 yakni 8,05%. Lebih rendahnya kadar serat kasar pada C0 karena tidak ada penambahan cassabio pada ransum tersebut sedangkan pada C10 karena taraf pemberian cassabio lebih rendah dari C30. Amrullah (2004) menyatakan tingginya kadar serat kasar mengakibatkan usus bekerja lebih aktif dalam mengatur kandungan air sel tubuh dan keseimbangan air. Tingginya kadar serat kasar pada C30 dapat mengakibatkan usus besar bekerja lebih sulit dalam mencerna ransum sehingga dapat mengakibatkan luka pada usus besar dan dapat mengakibatkan usus besar lebih panjang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ressang (1984) yang menyatakan radang usus ditandai dengan menurunnya nafsu makan dan menurunnya kondisi tubuh. Rasa nyeri pada radang mengakibatkan rangsangan atas ujung-ujung syaraf sensoris yang selanjutnya akan meningkatkan frekuensi dan intensitas peristaltik usus. Peningkatan intensitas peristaltik usus akan meningkatkan panjang usus tersebut. Selain itu, bobot hidup ayam broiler pada penelitian ini tidak berbeda secara statistik, sehingga ketika ukuran usus lebih panjang mengakibatkan nilai panjang relatif lebih tinggi. Menurut Grist (2006) usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari zat-zat makanan sebelum dibuang. 31 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penambahan cassabio dalam ransum penelitian berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal dan panjang relatif usus besar (P<0,05), namun tidak berpengaruh terhadap bobot hidup akhir, persentase karkas, hati, jantung, ginjal, pankreas, limpa, rempela, panjang relatif duodenum, jejunum, ileum, dan seka, sehingga cassabio dapat dijadikan salah satu pakan lokal alternatif. Berdasarkan kandungan lemak abdominal yang lebih sedikit sehingga lebih disukai oleh konsumen, sebaiknya kadar cassabio yang dicampurkan dalam ransum ayam broiler hingga taraf 20%. Saran Sebaiknya dilakukan pemisahan jenis kelamin (sexing) untuk menghindari pengaruh jenis kelamin sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, disarankan untuk analisa secara biologis untuk kandungan mikroba dalam saluran pencernaan. UCAPAN TERIMA KASIH Alhamdulillahirrobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, seminar, dan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Rasulullah SAW yang telah mengantarkan seluruh umat muslim menuju cahaya kebenaran dan ketaqwaan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Papah dan Mamah tercinta serta kakak-kakak tersayang (aa Anton, aa Andi, teh Lilis, dan teh Icha) yang selalu memberikan perhatian, semangat, motivasi, doa, dan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Ir. Iman Rahayu Hidayati Soesanto, MS. dan Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan yang begitu sabar kepada penulis, hingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si., Ir. Widya Hermana, M.Si., dan Dr. Jakaria, S.Pt.,M.Si. selaku dosen penguji serta kepada Dr. Rudi Afnan, S.Pt., M.Sc.Agr. sebagai pembahas seminar dan Ir. Lucia Cyrillia, M.Si. yang telah memberikan masukan, saran, dan pemahaman dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada Dr. Ir. Asnath Maria Fuah, MS. selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi selama penulis menempa berbagai ilmu di Fakultas Peternakan IPB. Terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Peternakan IPB atas bantuan dan bimbingannya. Kepada teman-teman seperjuangan penelitian Dimas, Pitriyatin, Raymundus, dan Pak Yanto terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk Evi, Ridha, Listi, Yandhi, Agung, Arfan, Dani, Asep, dan rekan-rekan IPTP 43 atas bantuannya. Terima kasih untuk sahabat tercinta Rola-D (FA 43), Kahfi Group, BEM-D 2009, Abadi Farm, Iit, Mail, Indra, Yudhi, Pondok Al Izzah, dan semua pihak yang terkait atas bantuan dan doanya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin. Apabila terdapat kesalahan penulisan dan kekhilafan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Bogor, Desember 2010 Gagah Hendra Wijaya DAFTAR PUSTAKA Akoso, B.T. 1993. Manual Kesehatan Unggas. Kanisius, Yogyakarta. Amrullah, I.K. 2004. Nutrisi Ayam Broiler. Cetakan ke-2. Lembaga Satu Gunungbudi, Bogor. Anggorodi, R. 1985. Ilmu Makanan Ternak Unggas Kemajuan Mutakhir. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Anwar, K.P., J. Nugraha, & Kurnia. 1985. Prospek pemanfaatan zeolit asal bayah sebagai penukar kation. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Pusat Pengembangan Teknologi Mineral, Jakarta. Becker, W.A., J.V. Spencer, L.W. Mirish, & J.A. Verstate. 1981. Abdominal and carcass fat in five body strain. Poultry Science. 60 : 693 – 697. Bell, D.D. & W.D. Weaver. 2002. Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5th Edition. Springer Science+Business Media, Inc. Spiring Street, New York. Blakely, D. & D.H. Bade. 1991. Ilmu Peternakan. Edisi ke-4. Penerjemah : Bambang Srigandono. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dewi, H.R.K. 2007. Evaluasi beberapa ransum komersial terhadap persentase bobot karkas, lemak abdomen, dan organ dalam ayam broiler. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ensminger, M.E., J.E. Oldfield, & W.W. Heinemann. 1992. Feed and Nutrition. 2nd Edition. Ensminger Publishing Company, California. Fontana, E.A., D. Weaver, D.M. Denbaow, & B.A. Watkins. 1993. Early feed restriction of broiler : effect on abdominal fat pad, liver, and gizzard weight, fat deposition, and carcass composition. Poultry Science. 72 : 243 – 250. Frandson, R.D. 1992. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Edisi ke-4. Penerjemah : Srigandono dan K. Preseno. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Frazier, W.C. & D.C. Weshoff. 1978. Food Microbiology. Mc Graw Hill Book.Co., New York. Garraway, M.O. & R.C. Evans. 1984. Fungal Nutrition and Physiology. John Wiley and Sons, New York. Gaspersz, V. 1991. Metode Perancangan Percobaan. Cetakan ke-2. CV Armico, Bandung. Grist, A. 2006. Poultry Inspection. Anatomy, Physiology, and Disease Conditions. 2nd Edition. Nottingham University Press, United Kingdom. Haroen, U. 1993. Pemanfaatan onggok dalam ransum dan pengaruhnya terhadap performans ayam broiler. Tesis. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. 34 Iyayi, E.A. & D.M. Losel. 2001. Protein enrichment of cassava by products through solid state fermentation by fungi. The Journal of Food Technology in Africa. 6 : 116-118. Leeson, S. & J.D. Summers. 2000. Broiler Breeder Production. University Books, Guelph, Canada. Lehninger, A. W. 1991. Dasar-Dasar Biokimia. Volume ke-1. Erlangga. Jakarta. Lubis, A.D., Suhartono, B. Darmawan, H. Ningrum, I. Y. Noormasari, & N. Nakagoshi. 2007. Evaluation of fermented cassava (Manihot esculenta Crantz) pulp as feed ingredient for broiler. Journal of Tropics. 17 : 73-80. Mc Lelland, J. 1990. A Colour Atlas of Avian Anatomy. Wolfe Publishing Limited, England. Murugesan, G.S., M. Sathishkumar, & K. Swarninathan. 2005. Suplementation of waste tea fungal biomass as a dietary ingredient for broiler chicken. Bioresource Technol. 96 : 1743-1748. Noormasari, I.Y. 2000. Pengaruh berbagai taraf penggunaan komplek onggok-ureazeolit dalam ransum terhadap persentase karkas, organ dalam, dan lemak abdominal ayam broiler. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pandey, A., C.R. Soccol, P. Nigman, V.T. Soccol, L.P.S. Vanderberghe, & R. Mohan. 2000. Biotechnologycal potential of agroindustrial residual II: cassava bagase. Bioresource Technology. 74 : 81-87. Pesti, G. M. & R. L. Bakali. 1997. Estimation of the composition of broiler cascasses from their specific gravity. Poultry Science. 76 (7) : 948-951. Phong, N.V., N.T.H. Ly, N.V. Nhac, & P.T. Hang. 2003. Protein enrichment of cassava by-product using Aspergillus niger and feeding the product to pigs. Agric. Biol. Chemi. 46 : 1667-1669. Piliang, W.G. & S.Al Haj Djojosoebagjo. 1990. Fisiologi Nutrisi Volume ke-1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat IPB, Bogor. Pitriyatin. 2010. Peningkatan protein onggok-urea-zeolit yang difermentasi oleh Aspergillus niger (cassabio) dengan penambahan amonium sulfat sebagai sumber sulfur. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pond, W.G., D.C. Church, & K.R. Pond.1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th Edition. John Wiley and Sons, New York. Putnam, P.A. 1991. Handbook of Animal Science. Academy Press, San Diego. Ressang, A.A. 1984. Patologi Khusus Veteriner. Edisi ke-2. CV Percetakan Bali, Denpasar. Soeparno. 1994. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press, Yoyakarta. 35 Sturkie, P.D. 2000. Avian Physiology. 4th Edition. Springer–Verlag, New York. Subronto. 1985. Ilmu Penyakit Ternak I. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Suhartono. 2000. Perubahan kualitas onggok-urea-zeolit fermentasi (cassabio) pada lama fermentasi yang berbeda. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Suprijatna, E., U. Atmomarsono, & R. Kartasudjana. 2008. Ilmu Dasar Ternak Unggas. Cetakan ke-2. Penebar Swadaya, Jakarta. Taram. 1995. Pengaruh lama fermentasi dan jenis kapang terhadap perubahan kandungan onggok zat-zat makanan onggok. Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Wahju, J. 2004. Ilmu Nutrisi Ternak Unggas. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 36 LAMPIRAN Lampiran 1. Hasil ANOVA Bobot Hidup Akhir Sumber Keragaman Perlakuan db JK KT 4 286.300 71.575 Galat 35 987.900 28.225 Total 40 1.274.200 Fhit P 2,536 0,057 Lampiran 2. Hasil ANOVA Persentase Karkas Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 27,912 6,978 0,317 0,865 Galat 35 770,809 Total 40 798,721 Perlakuan 22,023 Lampiran 3. Hasil ANOVA Persentase Lemak Abdominal Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 2,965 0,741 2,970 0,033* Galat 35 8,736 0,250 Total 40 11,701 Perlakuan Keterangan : * Berbeda nyata (P<0,05) Lampiran 4. Uji Tukey Persentase Lemak Abdominal Subset Perlakuan Ulangan C20 8 1,311 C40 8 1,331 1,331 C30 8 1,521 1,521 C10 8 1,743 1,743 C0 8 a b 2,035 38 Lampiran 5. Hasil ANOVA Persentase Hati Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 1,123 0,281 2,031 0,112 Galat 34 4,700 0,138 Total 39 5,823 Perlakuan Lampiran 6. Hasil ANOVA Persentase Jantung Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,043 0,011 0,971 0,436 Galat 35 0,384 0,011 Total 40 0,427 Perlakuan Lampiran 7. Hasil ANOVA Persentase Ginjal Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,149 0,037 1,798 0,151 Galat 35 0,726 0,021 Total 40 0,875 Perlakuan Lampiran 8. Hasil ANOVA Persentase Limpa Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,005 0,001 1,220 0,320 Galat 35 0,037 0,001 Total 40 0,042 Perlakuan Lampiran 9. Hasil ANOVA Persentase Pankreas Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,032 0,008 0,706 0,593 Galat 35 0,392 0,011 Total 40 0,423 Perlakuan 39 Lampiran 10. Hasil ANOVA Persentase Rempela Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,143 0,036 0,873 0,490 Galat 35 1,435 0,041 Total 40 1,578 KT Fhit P 0,792 0,538 Perlakuan Lampiran 11. Hasil ANOVA Panjang Relatif Duodenum Sumber Keragaman Perlakuan db JK 4 1,107 0,277 Galat 35 12,224 0,349 Total 40 13,331 Lampiran 12. Hasil ANOVA Panjang Relatif Jejunum Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 6,105 1,526 2,021 0,113 Galat 35 26,434 0,755 Total 40 32,539 Perlakuan Lampiran 13. Hasil ANOVA Panjang Relatif Ileum Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 10,542 2,635 2,455 0,064 Galat 35 37,580 1,074 Total 40 48,122 Perlakuan Lampiran 14. Hasil ANOVA Panjang Relatif Seka Sumber Keragaman db JK KT Fhit P 4 0,416 0,104 2,492 0,061 Galat 35 1,460 0,042 Total 40 1,876 Perlakuan 40 Lampiran 15. Hasil ANOVA Panjang Relatif Usus Besar Sumber Keragaman db JK KT Fhit 4 0,254 0,064 4,164 Galat 35 0,534 0,015 Total 40 0,788 Perlakuan P 0,007* Keterangan : * Berbeda nyata (P<0,05) Lampiran 16. Uji Tukey Panjang Relatif Usus Besar Subset Perlakuan Ulangan a b C0 8 0,456 C10 8 0,500 C40 8 0,518 0,518 C20 8 0,556 0,556 C30 8 0,689 41