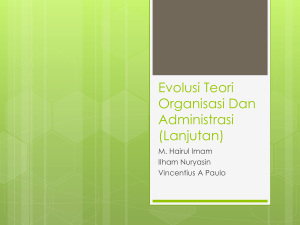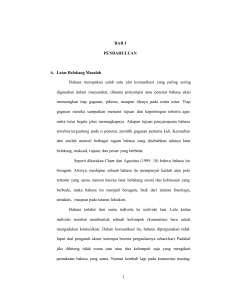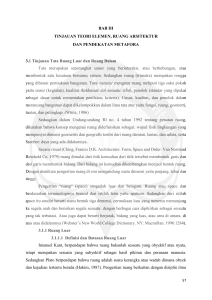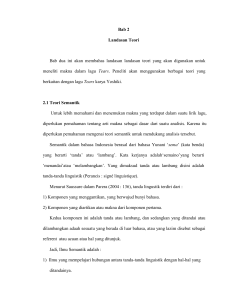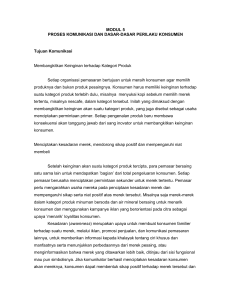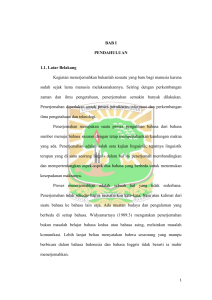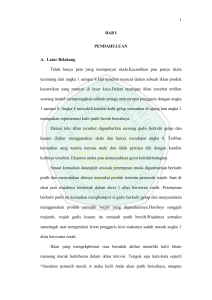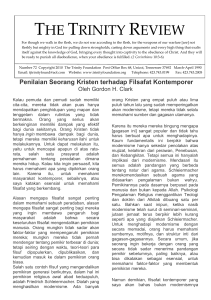SELAYANG PANDANG KAJIAN METAFORA Karya sastra
advertisement

1 SELAYANG PANDANG KAJ IAN METAFORA Karya sastra merupakan ekspresi perasaan sastrawan. Hal ini digarisbawahi oleh Sylvan Bernet bahwa “It holds that the artist is not essentially an imitator but a man who expresses his feelings”(1961:5). Maksudnya sastrawan bukanlah sekadar peniru tetapi orang yang mengekspresikan perasaannya terhadap kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Poetica, ketika sastrawan melihat kenyataan yang menampakkan diri sebagai sejumlah unsur yang kacau-balau, dia memilih beberapa unsur lalu menyusun suatu gambaran yang dapat dimengerti, yang menampilkan “kebenaran universal“, yang berlaku di mana-mana dan pada segala zaman (Aristoteles dalam Luxemburg, 1982:17). Dengan kata lain, karya sastra merupakan ekspresi perasaan sastrawan terhadap kenyataan yang diwujudkan dengan menggunakan media bahasa sebagai alat pencapai tujuan. Salah satu masalah dalam bahasa yang menarik untuk dicermati adalah pemakaian metafora dalam karya sastra. Salah satu misteri yang menyelimuti metafora ialah kebingungan publik jika mendapati ungkapan-ungkapan metaforis yang menyebutkan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya ingin diungkapkan. Kenyataan itu menyebabkan pengguna metafora terkesan sebagai pembohong atau penipu. Ketika Juliet berkata kepada Romeo “Cahaya yang bersinar dari matamu”, dia tentu saja tidak bermaksud untuk mengungkapkan bahwa dari bola mata Romeo bersinar cahaya yang menerangi ruangan tempat mereka berada. Ketika seorang penyair mengatakan,”Puisi adalah seekor burung”, dia tidak bermaksud untuk mengungkapkan bahwa puisi bisa mengepakkan sayap dan punya ekor. Dua contoh ini hanya sebagian contoh dari banyaknya contoh yang mengesankan metafora sebagai ungkapan yang penuh “absurditas” dan “kepalsuan” (Max Black dalam Ortony, 1993:21). Meskipun demikian apa yang dikatakan oleh anggapan umum publik tersebut menurut para linguis justru merupakan ciri mendasar yang secara tepat menjelaskan pikiran dan perasaan sastrawan. Bagi kalangan ini, metafora memudahkan baik sastrawan maupun pembaca karya sastra untuk menyentuh dimensi lain yang lebih dalam. Lebih dalam dari apa yang terungkap secara literal. Sebelum wacana tentang metafora sering dibicarakan , menurut Andrew Ortony (1993:1) telah tertanam persepsi bahwa ungkapan literal merupakan alat yang paling memadai dan sesuai untuk memerikan karakterisasi realitas secara objektif. Dalam perkembangan ilmu filsafat abad kedua puluh, ungkapan literal merupakan asumsi yang mendasari berkembangnya teori tentang makna. Kemudian salah satu puncaknya ialah dengan munculnya doktrin positivisme logis, yang berkembang pesat dikalangan filsuf dan ilmuwan lima puluh tahun yang lalu. Ide dasar aliran positivisme ialah realitas hanya bisa diperikan secara tepat melalui medium bahasa dengan cara 2 yang jelas, tidak mendua dan secara prinsip bisa diuji dan secara realistis dan literal harus bisa dijelaskan. Penggunaan bahasa yang menyimpang dari doktrin ini merupakan penggunaan bahasa yang tidak berarti. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang menyalahi kriteria pemaknaan yang bersifat empiris ini. Bagaimanapun sebuah teori dikembangkan, model pendekatan yang lain bisa dimunculkan, yaitu model pendekatan baru yang berbeda dengan model pendekatan yang sebelumnya. Inti gagasan model pendekatan itu ialah proses kognitif yang merupakan hasil konstruksi mental. Pengetahuan atas realitas, apakah itu didatangkan oleh persepsi, bahasa, atau pengetahuan yang merupakan hasil-hasil yang sifatnya jauh melampaui informasi yang diberikan dalam bentuk ungkapan kalimat. Hal itu muncul melalui interaksi wujud kalimat tersebut dengan konteks yang disajikan dan dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh pemakai bahasa. Pandangan umum ini merupakan pandangan relativis yang melihat dunia obyektif yang tidak bisa secara langsung diketahui, tetapi dibangun atas dasar pengaruh pengetahuan manusia dan bahasa. Dalam pandangan ini bisa disimpulkan bahwa bahasa, persepsi, dan pengetahuan manusia adalah saling bergantung dan berkait satu sama lain (Ortony, 1993:1). Fenomena metafora sejauh ini telah menarik perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, antropologi, dan kritik sastra. Pengkajian metafora di dalam disiplindisiplin itu terutama mengkaji metafora sebagai suatu proses kognitif, yaitu proses persepsi dan proses berpikir, dan bukan sebagai proses kebahasaan (Dirven dalam Paprotte dan Dirven, 1985:85). Para ahli filsafat (misalnya Nietzsche) menyatakan bahwa semua kegiatan berpikir pada dasarnya adalah berpikir secara metaforis; sedangkan para ahli psikologi (misalnya, H.Werner, 1919) menyatakan bahwa metafora sebagai instrumen yang paling baik bagi masyakarat primitif untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena alam yang terjadi di sekelilingnya. Para ahli antropologi (di antaranya Levi Strauss, 1962 dan Cassirer, 1968) menyatakan bahwa berdasarkan proses berpikir metaforis, metafora telah membantu membentuk bahasa dan juga mitos (lihat Dirven dalam Paprotte dan Dirven, 1985:86). Pada perkembangan yang mutakhir sering dibicarakan pengkajian metafora berdasarkan pendekatan kognitif seperti yang diungkapkan oleh George Lakoff (1980). Berdasarkan pendekatan itu, metafora dipandang sebagai suatu cara kategorisasi fakta-fakta pengalaman menurut ciri-ciri pengalaman yang telah dikenal. Di dalam sistem kognitif kita, kita membentuk kategori-kategori yang merupakan model-model kognitif ideal dari elemen-elemen pengalaman tertentu. Model-model itu membantu kita mengkategorikan pengalaman-pengalaman baru yang terus tumbuh dan meletakkan hubungan kognitif dengan pengalaman lama melalui proses metafora (lihat Dirven dalam Paprotte dan Dirven, 1985:86).