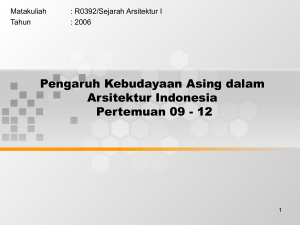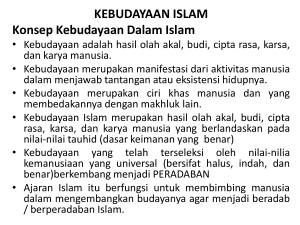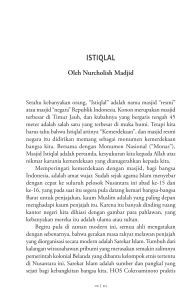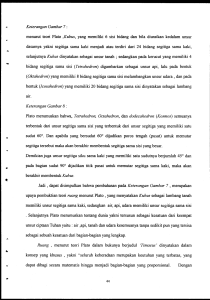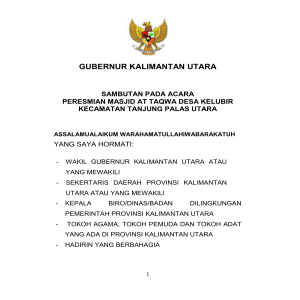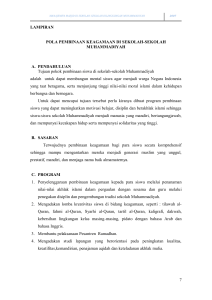pendidikan nasional harus mampu menjamin
advertisement

MADRASAH, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN Sebuah Dilema Baru Pasca Otonomi Daerah Oleh: Fauzan, MA1 Prolog Salah satu dampak positif dari reformasi bidang pemerintahan adalah terjadinya pergeseran paradigma politik pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik, yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pembagian Keuangaan antara Pusat dan Daerah. Lahirnya produk hukum tentang otonomi daerah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan RI, karenanya otonomi tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu kebebasan obsolut tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Karena itu, desentralisasi bukanlah merupakan sistim yang berdiri sendiri, melainkan dia merupakan rangkaian kesatuan dari suatu sistim yang lebih besar, yaitu Negara Kesatuan RI. Realitas ini tidak saja mengabaikan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11, Ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal tersebut tentu saja memasukkan di dalamnya adalah penyelenggaraan Pendidikan Agama. Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dijelaskan dalam bagian Menimbang point (c) disebutkan bahwa “sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 1 Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”. Sedangkan, layanan dan kemudahan seperti disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Atas dasar tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dengan tidak membedakan apakah pendidikan tersebut dikategorikan “umum” atau berbasiskan “agama”. Diperjelas lagi dalam Ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Masalah belum adanya perhatian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan agama tersebut muncul, banyak disebabkan oleh pemahaman, interpretasi dan implementasi yang tidak komprehensif mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (3) poin (f) yang di dalamnya memuat tentang sentralisasi masalah “agama” oleh Pemerintah (Pusat). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan dalam menumbuhkembangkan kehidupan keagamaan”. Atas dasar Pasal 10 tersebut, banyak Pemerintah Daerah yang memahami bahwa penyelenggaraan Pendidikan Agama dengan merujuk dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat cq. Departemen Agama Republik Indonesia. Padahal, jika merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota” dikaitkan dengan poin (f) dalam pasal tersebut “penyelenggaraan pendidikan”. Karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Pusat dan adanya anggapan bahwa Pendidikan Agama bukan wewenang Pemerintah Daerah, menyebabkan Pendidikan Agama menjadi terabaikan, dan cenderung tidak diperhatikan, baik dalam konteks pembinaan tenaga guru, tenaga kependidikan, desain kurikulum, penyediaan sarana dan juga pendanaan penyelenggaraan pendidikan agama di daerah. Dengan demikian masalah pendidikan agama dan keagamaan yang di kelola Departemen Agama menjadi posisi yang remang-remang dan bila hal ini tidak terperhatikan maka dia dapat merugikan berbagai fihak, terutama para penyelenggara dan peserta didik dilingkungan Departemen Agama. Madrasah, Pendidikan Keagama, dan Pesantren Madrasah Menurut Munir Ud-Din Ahmed yang juga dikutip oleh Azyumardi, sebelum munculnya madrasah, pendidikan muslim sejak masa Nabi Muhammad berlangsung terutama di seputar masjid dan rumah guru. Pendidikan dilaksanakan dalam halaqoh, majlis alo-Tadris, dan kuttab 2 . Pendidikan madrasah merupakan pengembangan dari pendidikan yang sudah ada sebelumnya, menurut hemat penulis, dilihat dari kronologi sejarahnya, pendidikan Islam disampaikan pertama kalinya mulai dari rumah, lalu seiring dengan berkembangnya Islam dan terbentuknya masyarakat muslim maka masjid dijadikan tempat pendidikan berikutnya. Selanjutnya dengan makin banyaknya peminat (pelajar) dan juga pengetahuan tentang keagamaan makin merata sehingga sering kali terjadi soal-jawab dan debat dalam masjid yang mengganggu suasana ketenangan masjid sebagai tempat ritual vertikal khususnya, maka muncullah kuttab 3 sebagai implikasi-logis suasana masjid yang tidak begitu kondusif. Syalabi menggambarkan ini: Sejak masa awal Islam, banyak orang berminat untuk mempelajari Islam. Bertambah tahun, semakin banyak orang yang menghadiri pertemuan untuk belajar ilmu (halaqah 'ilm). Dari setiap grup pertemuan terdengar suara dari seorang furu yang memberikan pelajarannya dan dari suarasuara peserta didik yang bertanya dan saling berdebat. Maka terjadilah suara keras dari beberapa frupo pertemuan itu. Sedikit banyak hal itu menimbulkan gemuruh yang mengganggu pelaksanaan 2 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), Cet.IV, h.11 3 Menurut Asma Hasan Fahmi, Kuttab merupakan Institusi pendidikan Islam yang didirikan oleh orang Arab pada masa Abu BAkar dan Umar. Kemunculan Institusi ini berkaitan dengan keberhasilan orang-orang Arab muslim menguasai wilayah-wilayah baru. (lihat: Asma Hasan Fahmi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, terj. Ibrahim Husen, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Cet.1, h.30 ibadah sebagai mestinya. Jelaslah masjid menjadi sulit untuk dijadikan tempat ibadah dan tempat belajar sekaligus4. Menurut George Makdisi, perpindahan lembaga pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung, tetapi melalui tahapan perantara, yaitu masjid. Lebih lanjut ia mengemukakan teori, bahwa asal muasal pertumbuhan madrasah merupakan hasil tiga tahap: tahap masjid, tahap masjid khon, dan tahap madrasah.5 Masjid dalam tahap pertama yang dimaksud adalah masjid biasa, bukan masjid jami yang biasanya didirikan oleh pemerintah. Karena biasanya masjid seperti itu tidak terbuka untuk pendidikan agama bagi umum. Sedangkan yang dimaksud dengan masjid khon adalah masjid yang dilengkapi fasililtas menginap, seperti asrama atau pemondokan. Letaknya biasanya bergandengan ataudekat dengan masjid itu sendiri. Tahap selanjutnya terntulah madrasah yang menjadi lembaga pendidikan sebagai pengembangan dari masjid dan kuttab. Lain lagi halnya dengan Ahmad Syalabi, Menurutnya perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung, tidak memakai lembaga perantara.6 Nampaknya, Syalabi melihat adanya madrasah merupakan implikasi logis dari semakin ramainya kegiatan pengajian di masjid dan juga hal yang wajar dari kemajuan pemikiran karena pengaruh perkembangan zaman yang tidak menutup kemungkinan perlunya ada inovasi-inovasi tertentu. Munculnya madrasah ini nampaknya sudah ada sejak zaman Abbasiyah, sebagaimana sedikit telah disinggung di atas. Hassan Muhammad Hassan dan Nadiyah Muhammad Jamaluddin menyebutkan lima sistem pendidikan yang ada pada abad keempat hijrah dengan pendeskripsian sebagai berikut: 1. Filosof menggunakan: Dar al-Hikamah, al-Muntadiyat, Hawanit dan Warraqin. 2. Orang-orang sufi menggunakan: al-Zawaya, al-Masajid dan Halaqot al-Dzikr. 3. Orang-orang Syiah menggunakan: Dar al-Hikmah, al-Masajid, al-Maktabat, Hawanit, alWarraqin, dan al-Muntadiyat. 4 Ahmad Syalabi, al-Tarbiyah al-Islamiyah, Nuzumuha, falsafatuha, Tarikhuha (Kairo, Maktabah alNahdah al-Mishriyah, 1987), Cet. 1, h.43 (dalam footnote "Madrasah Sejarah dan perkembangan", karya: Dr. H. Maksum, h. 55) 5 George Makdisi, Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad, dalam Buletting of the School of oriental and African Studies 25:1961, h. 1-56 (dalam footnote "Madrasah Sejarah dan perkembangannya", Karya: Dr. H. Maksum, H. 56-57) 6 Ahmad Syalabi, History of Muslim Education, (Beirut: Dar al-al-Kasyaf, 1954), h. 257-259 4. Mutakallimin menggunakan: al-Masajid, al-Maktabat, Hawanit, al-Warraqin, dan alMuntadiyat. 5. Fuqoha dan Ahli Hadist menggunakan: Al-Katatib, al-Madaris, al-Masajid.7 Meskipun istilah madrasah telah ada pada masa Abbasiyah, namun menurut Al-Suyuthi sebagai dikutip oleh Abu al-Falah, Istilah 'madrasah' baru digunakan agak luas sejak abad kesembilan masehi. Institusi yang memperlihatkan ciri-ciri madrasah sebagaimana dikenal sekarang, didirikan di Nisyapur, Iran, sekitar perempatan pertama abad kesebelas masehi.8 Kajian tentang sejarah munculnya madrasah pertama didunia Islam masih di debatkan. Syalabi menyatakan bahwa madrasah yang mula-mula muncul di dunia adalah Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham Al-Mulk, perdana mentri dari Saljuk, pada tahun 1065-1067 M/ (457- 459 H). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Phlilip.K.Hitti dalam bukunya "History of the Arabs" (lihat, Philip K. Hitti 1974:410). Sedangkan Richard W. Bulliet berpendapat bahwa dua abad sebelum Madrasah Nizamiyah muncul, di Nisapur (Naisabur) sudah berdiri madrasah, yaitu Miyan Dahiyah9 Athiyah Al-Abrasyi, mengutip dari Al-Maqrizi,10 mengemukakan bahwa madrasah al-Baihaqiyah adalah madrasah yang pertama didirikan pada akhir abad keempat hijrah (abad kesebelas Masehi).11 Hasal Abd al-'Al, yang secara khusus melakukan kajian mengenai pendidikan Islam pada abad keempat hijrah, mengemukakan bahwa madrasah telah berdiri sejak abad keempat hijrah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur. Ia memperkuat pendapatnya dengan mengajukan buktibukti berdasar karya penulis-penulis abad keempat sendiri. Beberapa sumber yang ia kutip antara lain Ahsan alTaqosim fi Ma'rifat al-"Aqolim karya al-Maqdisi (wafat 378 H), Tobaqot al-Syafi'iyah al-kubro karya al-Subki (316-388 H), al-Rasail karya Badi' al-Zaman al-Hamadani (wafat 398 H)12 7 Hassan Muhammad Hassan dan Nadiyah Jamaluddin, Madaris al-Tarbiyah fi al-Hadarah al-Islamiyat, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1988), Cet. I h. 16-23 (Dalam Footnote: "Madrasah Sejarah dan Perkembangannya", karya: Dr. H. Maksum, h. 52) 8 Abu Al-Falah ibn "Abd Al-Hay ibn Al-'Imad, Syadzarat al-Dzahab fi akhbar man Dzahab, 8 Jilid, (Kairo: Makatabat al-Quds, 1350) cet. II, h. 181-2 (Dalam Footnote, Azumardi Loct.cit h. 11) 9 Richard W. Bulliet, The Patrician of Nisaphur: a study in Medieval Islamic Social History, (Harvard: Harvard University Press, 1972) cet. I, h. 48 ( Dalam Footnote: Sejarah Pendidikan Islam, Karya: Hanun Asrohah, M.Ag, h. 100) 10 Al-Maqrizi adalah ahli sejarah di Dar al-'Ilm pada masa dinasti Fatimiyah (lihat: M. Yunus: 1966, h. 57) 11 Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terjemahan Bustami A. Gani dan Djohar Basri (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet. VII, h. 79 12 Maksum, Madrasah Sejarah danperkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II, h. 60. nampaknya pendapat Hasal ini berdekatan dengan Richard W. Bulliet, hanya saja ia tidak menyebutkan madrasah di Naisabur tersebut. Richard Bulliet menjelaskan bahwa madrasah di Nisapur ini, yang merupakan madrasah periode pertama (awal), nampaknya didirikan oleh ulama fiqh dengan tujuan utama mengembangkan ajaran mazhabnya. Miyan Dahiya merupakan madrasah tertuanya yang mengajarkan fiqh Maliki.13 Sementara Pendidikan Keagamaan dimaksudkan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama dan Keagamaan ini secara umum berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Selain itu, pendidikan agama dan keagamaan menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik dalam juga bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Secara operasional, pendidikan keagamaan bisa berupa diniyah dan pondok pesantren. Karena itu, ada yang bersifat format dan non-formal. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak seperti madrasah yang sudah secara eksplisit disebut di dalamnya, term pendidikan agama belum secara eksplisit muncul dalam pembahasan, sehinggan istilah pendidikan agama lebih diintegralisasikan dengan pelaksanaan pendidikan secara umum. Dengan kata lain bahwa istilah pendidikan agama menjadi kajian yang tidak dipisahkan dengan pendidikan secara umum sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan untuk pendidikan keagamaan, Undang-undang tersebut sudah menyebutkannya secara eksplisit, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1-5), yakni “Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Permasalahan Klise Pendidikan Islam Di kalangan umat Islam, masalah pendidikan mendapat perhatian khusus, karena berkembangnya Islam sendiri tidak lepas dari peran pendidikan yang begitu besar. Oleh karena itu 13 Richard W. Bulliet, The Patricians of Nishapur, (Cabridge: HUP, 1972),cet. I, h. 48 walaupun perkembangan politik suatu negara (Islam) sedang tidak menentu, atau singkatnya adanya perkembangan yang menutup ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah negaranya, maka bagi dunia pendidikan tetap saja terbuka. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang mendorong munculnya berbagai lembagalembaga pendidikan yang menawarkan berbagai jenjang. Ini merupakan pandangan profetis masyarakat khususnya kaum muslimin dalam merencanakan masa depannya menjadi lebih baik. Pandangan positif masyarakat tersebut di atas akan menjadi sia-sia jika tanpa didukung oleh pembaharuan di bidang pendidikan itu sendiri, dalam hal ini pendidikan Islam. Pendidikan Islam khususnya madrasah masih belum menunjukan perkembangan pembaharuan yang memuaskan. Madrasah ternyata masih kalah bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang berada dalam naungan Departemen Pendidikan Nasional. Sejalan dengan perkembangan Indonesia, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam juga terus berkembang namun perkembangan itu cukup eksklusif, di mana aksentuasi pada pengetahuan keagamaan (Islam) lebih diutamakan. Hal ini juga yang menyebabkan perkembangan madrasah hanya ada pada kantong-kantong masyarakat Islam. Ekspansi yang dilakukan pun hanya berkisar di daerah pedesaan sedangkan untuk di perkotaan sangat jarang. Oleh karena itu hingga saat ini keberadaan madrasah lebih banyak di pedesaan daripada di perkotaan. Dan hal ini juga yang memicu lambannya perkembangan madrasah, madrasah seakan jauh dari atmosfir pembaharuan sistem pendidikan, baik secara kelembagaan maupun sistem dari proses pembelajaran itu sendiri. Pada tahun 1994, perkembangan madrasah mengalami suatu periode yang sangat penting, di mana pada tahun tersebut Departemen Agama, tempat di mana madrasah bernaung memberlakukan sebuah kurikulum baru yang selanjutnya disebut "kurikulum 1994". Pada kurikulum tersebut mensyaratkan agar madrasah melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolahsekolah umum yang ada dalam naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-sekarang Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kurikulum 1995, di mana kurikulum madrasah memuat 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama Islam, maka pada kurikulum 1994 ini madrasah wajib melaksanakan 100% dari kurikulum yang dibebankan pada sekolah-sekolah umum. Sebagai konsekuensinya madrasah mesti menghapus 30% muatan pendidikan agama Islam dari kurikulumnya dan kedudukannya adalah setaraf dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang berada dalam naungan Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini telah ditegaskan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3, yaitu:14 Pasal 17 ayat 2 " Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat". Sedangkan pasal 18 ayat 3 yaitu, "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menegah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat." Di samping konsekuensi di atas, eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam pun mulai dipertanyakan masyarakat. Madrasah yang pada awalnya diharapkan akan mampu memunculkan ahli-ahli agama dan para pemimpin Islam mulai diragukan, apakah dengan kondisi yang seperti itu masih bisa. Seperti yang kita ketahui bahwa paling tidak, ada tiga fungsi tradisional madrasah, yaitu; pertama, sebagai media penyampai pengetahuan agama (transfer of Islamic knowledge), kedua, sebagai media pemelihara tradisi Islam (maintenance of Islamic tradition) dan yang ketiga, sebagai media pencetak ulama (reproduction of ulama).15 Walupun mempunyai kedudukan yang setingkat dengan sekolah-sekolah umum, perjalanan madrasah tetap berbeda dengan sekolah-sekolah umum tersebut. Madrasah masih dianggap lembaga pendidikan "kelas dua", di mana ada pandangan "daripada tidak sekolah lebih baik masuk madrasah". Ironisnya pandangan ini muncul dari kalangan umat Islam sendiri. Namun apakah mereka patut disalahkan? Selama madrasah tidak mampu membenahi dirinya agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka mereka tidak dapat disalahkan. Perbedaan mencolok antara madrasah dan sekolah-sekolah umum selain dapat dilihat dari tradisi proses pembelajaran juga akses para alumni terhadap perguruan tinggi dan dunia kerja. Tradisi proses pembelajaran di madrasah yang lebih memperhatikan gaya-gaya tradisional di mana 14 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, 2003 tentang Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 9 15 Jurnal Madrasah, Vol. I, No. 4, 1998, h. 6 proses pembelajaran lebih didominasi oleh para pendidik atau guru, juga diwarnai dengan kualitas tenaga pengajar yang kurang memadai. Banyak tenaga pengajar yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dilihat dari akses lulusan, ini sangat berbeda dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum di mana mereka memiliki akses yang lebih terbuka untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi umum, sementara bagi lulusan madrasah, keterbukaan itu hanya ada pada perguruan-perguruan tinggi Islam. Dari segi akses ke lapangan kerja, tampaknya kalangan dunia usaha lebih mempercayai lulusan sekolah-sekolah umum daripada madrasah. Lulusan sekolah-sekolah umum lebih mampu bersaing dengan lulusan dari madrasah.16 Ini merupakan permasalahan besar bagi para pemerhati dan para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal muatan pelajaran umum antara mdrasah dengan sekolah-sekolah umum adalah "sama", pada kasus ini sebenarnya madrasah masih memiliki keunggulan karena muatan pendidikan agama jelas lebih banyak daripada sekolah-sekolah umum, ini berarti pendidikan moral yang dikandung dalam pendidikan agama lebih banyak diberikan pada madrasah. Namun persoalan selanjutnya adalah kenapa dengan keunggulan tersebut madrasah masih kurang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Dari keterangan-keterangan di atas nampak adanya persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi madrasah. Persoalan-persoalan tersebut mulai dari kurikulum, managemen, tenaga pengajar, proses pembelajaran, sarana prasaran, adanya persoalan atau konflik antara tradisi pemikiran dan pendidikan Islam dengan modernitas, adanya anggapan negatif masyarakat terhadap madrasah seperti yang disinggung di atas, persoalan kelembagaan hingga pada persoalan legalitas hukum keberadaan madrasah. Dalam pembahasaan ini, persoalan-persoalan tersebut menjadi ladang pembaruan pendidikan Islam. Persoalan pertama, kurikulum bagi suatu madrasah bukanlah hal yang bisa diremehkan begitu saja, karena pada hakekatnya kurikulum adalah "ruh" dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan sutau pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang tepat maka akan sulit untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah 16 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), cet. ke-2, h. 57 digariskan.17 Kurikulum di madrasah yang sarat materi (overloaded) dan bahkan tidak memiliki keterkaitan di antara mata pelajaran-mata pelajaran yang ada, lagi pula kurikulum tersebut lebih ditekankan pada ranah kognitif sementara ranah afektif dan psikomotorik menjadi terabaikan, kondisi ini jelas merupakan area pemabaharuan yang mesti cepat dilakukan. Belum lagi persoalan kesesuaian antara kebutuhan user atau masyarakat dengan konsep kurikulum yang ada sekarang ini masih belum mencerminkan sebuah Persoalan kedua, adalah managemen. Seperti diketahui bahwa managemen adalah "ruh" bagi jalannya suatu roda organisasi, termasuk juga madrasah. Persoalannya muncul ketika madrasah didirikan oleh perorangan dan yayasan keagamaan, hal ini karena pihak pendiri berkedudukan sebagai "pemilik" di mana segala kegiatan yang dilakukan harus dengan seizinnya. Pada kasus ini, muatan intervensi khususnya dari orang-orang yang merasa lebih berjasa terhadap pendirian madrasah sulit dihindari, apalagi jika lahan yang digunakan untuk madrasah tersebut adalah lahan miliknya pribadi. Hal ini mengakibatkan "rancuh"nya suatu managemen yang diterapkan pada madrasah tersebut. Padahal managemen menduduki posisi vital terhadap eksistensi suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah. Sulit dibayangkan suatu madrasah akan maju, berkembang, menjadi center of excellence dan mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya jika tidak memiliki managemen pendidikan yang tangguh. Persoalan ketiga adalah tenaga pengajar atau pendidik atau sering juga disebut guru. Keberadaannya merupakan komponen penting dalam pendidikan, karena itu guru adalah garda terdepan dalam dunia pendidikan. Ia merupakan jabatan profesi yang mengabdikan jasanya dalam dunia pendidikan. Ia juga merupakan motor penggerak roda pendidikan. Seorang tenaga pengajar atau guru diharapkan mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif sehingga mampu mengembangkan daya kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.18 Pada madrasah banyak sekali guru yang mengajar bukan pada bidang keahliannya. Di sini aspek profesionalisme guru menjadi terabaikan. Mungkin hanya pada madrasah-madrasah yang 17 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. ke-1, h. 3 18 H.M. Irsyad Djuwaeli, Pembaharuan Kembali Pendidikan Islam, (Ciputat: Yayasan Karsa Utama Mandiri dan PB. Mathlaul Anwar, 1998), cet. ke-1, h. 20-21 sudah maju saja yang sudah mensyaratkan agar guru yang mengajar haruslah profesional dalam bidangnya. Persoalan keempat adalah menyangkut proses pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran di sini merupakan interaksi antara komponen-komponen pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu hubungan yang saling mendukung. Komponen-komponen tersebut paling tidak meliputi guru, media, ruang dan peserta didik itu sendiri. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Jika salah satunya tidak ada atau katakanlah tidak dapat berfungsi maksimal, maka dapat ditebak proses pembelajaran tidak akan berjalan maksimal. Pada madrasah yang terjadi adalah proses pembelajaran di man guru menjadi faktor sentral, ia menjadi sumber utama pembelajaran. Bahkan proses pembelajaran menjadi superfisialisasi proses pendidikan, di mana dari luar tampak serius akan tetapi sebenarnya tidak memiliki bobot seperti yang diharapkan. Dalam hal ini telah terjadi banyak kepura-puraan baik yang dilakukan oleh pendidik maupun oleh peserta didik itu sendiri. Untuk itu aksentuasi proses pembelajaran pada peserta didik mesti ditegaskan kembali. Persoalan kelima adalah sarana prasarana. Persoalan ini terutama menyangkut "tempat" di mana proses pendidikan itu diselenggarakan. Kita sering mendengar banyaknya tempat-tempat belajar termasuk juga madrasah yang keberadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Dalam hal ini banyak sekali sarana dan prasarana pada madrasah sudah tidak memadai. Kondisi bangunan yang kurang layak bagi proses pendidikan nampaknya sudah menjadi pemandangan bagi madrasah, biasanya mereka masih bisa menghibur diri dengan mengatakan yang penting adalah kualitas proses pembelajarannya. Kalau diamati secara lebih cermat bagaimana proses pendidikan mau berkualitas jika sarana dan prasarananya tidak mendukung. Oleh karena itu berkaitan dengan sarana dan prsarana pendidikan adalah bagaimana menjadikan peserta didik "betah" di madrasah, menjadikan madrasah rumah keduanya pendek kata menjadikan madrasah sebagai tempat yang aman dan nyaman. Sehingga hal ini akan membuat peserta didik senang berlama-lama berada di madrasah. Persoalan keenam adalah adanya persoalan atau konflik antara tradisi pemikiran dan pendidikan Islam dengan modernitas, ini bermula dari pandangan bahwa modern sama dengan Barat. Barat sudah terlanjur di cap negatif, adanya pergaulan bebas, sex bebas dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Islam dianggap datang dari Barat. Untuk itu hal-hal yang berbau Barat ditolak. Pandangan ini sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan Belanda sendiri ada pada golongan Barat. Ciri-ciri modernitas yang sering tidak cocok yang sering tidak cocok dengan pemikiran pendidikan Islam antara lain; 19 paradigma modernitas yang bertolak pada rasionalitas, individualitas, kajian-kajian atau inquery scientific yaitu penelitian kajian ilmiah yang lebih menekankan pada lapangan kerja setelah peserta didik menyelesaikan masa pendidikannya. Ini sangat berbeda sekali dengan tradisi Isalm, di mana pekerjaan bukanlah merupakan hal yang penting, karena yang terpenting adalah proses mencari ilmunya, sedangkan persoalan pekerjaan adalah persoalan kemudian. Persoalan ketujuh adalah adanya anggapan negatif sebagian masyarakat. Anggapan tersebut bermula dari kurang mampunya madrasah memecahkan persoalan-persoalan di atas. Anggapan tersebut dapat berupa bahwa madrasah kurang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum, perlengkapan belajar yang masih kurang memadai, kurikulum yang overloaded, peluang lulusan dari madrasah terhadap perguruan-perguruan tinggi umum dan dunia kerja lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum hingga adanya anggapan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua. Persoalan kedelapan, adalah masalah kelembagaan. Kelembagaan pada suatu lembaga pendidikan menjadi signifikan karena adanya pembaharuan dimulai dari kemauan dan kesiapan lembaga tersebut. Derasnya gelombang pembaharuan tanpa diiringi kemauan dan kesiapan suatu lembaga maka perubahan tersebut tidaklah mempunyai arti, karena dominasi suatu lembaga pendidikan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan sangat kuat. Pendidikan Islam dan Otonomi Daerah 19 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi, (Jakarta: Kompas, 2002), cet. ke-1, h. 119-120 Kebijakan pengelolaan pendidikan agama, sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pelaksanaan pendidikan secara umum, karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan agama di daerah masih saja mendapatkan perlakuan yang “diskriminatif” dari pemerintah daerah. Hal ini banyak disebabkan masih belum komprehensifnya pemahaman pemerintah daerah pada terminologi “pendidikan” dan “agama” yang termuat dalam kedua Undang-undang tersebut, sehingga banyak memunculkan penafsiran secara parsial bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Sementara, pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama yang berbentuk Madrasah dan sekolah agama lainnya belum banyak diterima sebagai bagian dari pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik dalam konteks bimbingan maupun dalam konteks subsidi pendanaan pendidikan. Secara yuridis formal, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah untuk memberdayakan daerah, yakni dengan memberikan kewenangan tertentu bagi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang dibutuhkan demi kesejahteraan/ keselamatan semua. Ini berarti bahwa pusat memberikan kepercayaan atau percaya kepada daerah dan menghargai kemampuan dan “jati diri” daerah. Di samping itu, sesuai dengan spirit otonomi daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah sebagai realisasi atas pengakuan akan kebhinekaan di daerah juga meniscayakan adanya pelaksanaan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai bentuk keterlibatan dan kepedulian pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing. Salah satu hal yang yang terkandung dalam prinsip otonomi daerah adalah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan orang tua. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat, masyarakat dan orang tua dalam mengalokasikan anggaran (pembiayaan) untuk penyelenggaraan pendidikan. Pada tataran selanjutnya, otonomi pendidikan tidak sekadar dipahami sebagai pemindahan wewenang penyelenggaraan pendidikan dari departemen kepada sekolah dan masyarakat, tetapi juga mengandung makna pemberdayaan lembaga pendidikan dalam melakukan inovasi dan rekayasa organisasi untuk meningkatkan kinerja sekolah dan madrasah. Peran serta masyarakat dalam manajemen pendidikan dasar dan menengah diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pendidikan (school council) di tingkat Nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sementara di tingkat sekolah dan madrasah, peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah (school committee) (Ramly, 2005: 49). Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan memerlukan pola pembiayaan yang tidak diskriminatif dan harus mencerminkan keadilan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan subsidi silang, imbal swadaya, block grant, dan menerapkan formula subsidi kontekstual. Subsidi silang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghindari timbulnya kesenjangan antara sekolah (madrasah) daerah miskin dan daerah kaya. Imbal swadaya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah untuk mendorong berkembang dan meningkatnya program-program yang menjadi unggulan pusat dan daerah. Block grant dapat diberikan dengan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas program-program yang memiliki prospek untuk berkembang lebih lanjut dengan cara berkompetisi. Pelaksanaan otonomi pendidikan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pendidikan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka kebijakan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelumnya hanya Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang berada di bawah naungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional. Penyerahan kewenangan pendidikan dari pusat (Departemen Pendidikan Nasional) ke pemerintah daerah bukan hanya sekadar dilihat dari sisi pembiayaan pendidikan, tetapi juga secara keseluruhan penyelenggaraan teknis pendidikan di daerah. Dalam konteks ini maka selain kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), maka pelaksanaan pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kesimpulan Dari uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa madrasah, diniyah, wustho, ma’had ‘aly dan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan yang lahir dari bagian masyarakat menjadi sebuah dilemma manakala keberadaanya tidak diperhatikan. Walaupun banyak persoalan menyangkut keberadaan madrasah, baik menyangkut kesiapan SDM, manajemen, pembiayaan dan sebagainya, namun semua itu dapat diatasi ketika semua pihak bersatu padu memberikan kontribusi posistif demi sebuah kemajuan bersama. Ide pengembangan tersebut tidak saja diperlukan dari masyarakat setempat, namun dari semua lapisan masyarakat di penjuru Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, orang tua siswa, dan terlebih lagi sikap pemerintah dalam membuat kebijakan tidak lagi diskriminatif, karena bagaimanapun juga baik madrasah, diniyah dan pesantren merupakan bagian integrative dari pendidikan nasional.