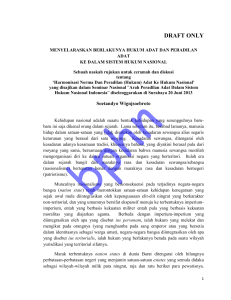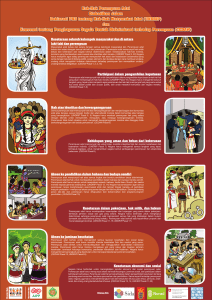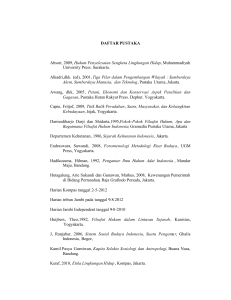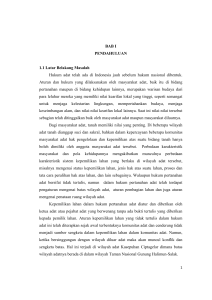Peranan Lembaga Adat
advertisement

Potret Pergulatan Lembaga Adat Tuva dan Marena dalam Menjamin Akses atas Tanah Bernadinus Steni Abstrak Akses terhadap tanah merupakan keinginan sebagian besar warga di dua lokasi penelitian dalam tulisan ini yang, meskipun sudah diperjuangkan sejak lama, sulit terwujud karena ada kebijakan pemerintah yang membatasi akses tersebut. Karena itu, isu kunci studi ini adalah bagaimana masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat berjuang membuka akses atas tanah. Di sini salah satu forum utama yang berperan memperjuangkan akses tersebut adalah lembaga adat. Lembaga adat dalam penelitian ini adalah lembaga yang sehari-hari rutin berhubungan dengan masyarakat dan memainkan peranan penting dalam mendistribusikan tanah dibandingkan dengan forum-forum lain, seperti BPN dan Balai Taman Nasional. Di dua lokasi penelitian ini, peranan lembaga adat masih diakui masyarakat adat meskipun operasionalisasinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi bekerjanya lembaga adat dalam menjamin akses warga adat atas tanah adalah: pengetahuan hukum adat, status sosial, cakupan jaringan yang dimiliki para pemangku atau tokoh-tokoh lembaga adat, informasi yang diperoleh warga masyarakat adat, relasi lembaga adat dengan institusi negara, ketaatan warga masyarakat adat, sikap dan perilaku migran, tanggapan birokrat lapangan, kepentingan ekonomi masing-masing aktor. Studi ini dilakukan di Dusun I Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa dan Dusun Marena Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, keduanya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Warga kedua dusun ini dihuni oleh berbagai etnis, tapi ada etnis tertentu yang mengklaim dirinya sendiri sebagai masyarakat adat. Klaim mereka didasarkan pada argumen historis bahwa mereka adalah orang-orang yang merupakan penghuni pertama wilayah tersebut. Di Dusun I Tuva berdiam masyarakat adat Sinduru, sementara di Marena terdapat orang Kulawi sebagai masyarakat adat. Warga kedua dusun, baik adat maupun migran, mengalami persoalan akses atas tanah karena sebagian besar kawasan yang dulunya mereka manfaatkan untuk berkebun dan mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan rumah tangga, sejak era 1970-an hingga sekarang telah ditetapkan Departemen Kehutanan sebagai hutan lindung, hutan produksi dan taman nasional. Pemerintah Daerah juga mengambil sebagian wilayah Marena sebagai areal perkebunan. Situasi-situasi ini merupakan pengalaman warga yang mendorong mereka dengan berbagai cara mendapatkan hak atas tanah. Lembaga adat adalah salah satu forum yang dituju maupun digunakan warga untuk mendapatkan akses atas tanah. Sebaliknya, lembaga adat mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam berbagai bentuk, baik dengan menggunakan otoritasnya sendiri, menggandeng otoritas lain atau mengajukan ke otoritas yang lebih kuat (lembaga negara). Karena itu fokus studi ini adalah menyangkut faktor dan aktor yang mempengaruhi bekerjanya lembaga adat sebagai forum yang dituju warga untuk mendapatkan akses atas tanah. Pendahuluan Penelitian ini dilakukan di Dusun Marena dan Desa Tuva, dua daerah yang multietnis di Sulawesi Tengah. Penduduk Marena, yang menurut data 2001 dihuni oleh 60 kepala keluarga atau 230 jiwa, sebagian besar berasal dari Kulawi yang berbahasa Moma. Selebihnya berasal dari Rampi, Seko, Toraja, Bugis, Mandar, Pekurehua, Bada, Kaili, Da’a, Manado, Jawa dan etnis 1 Kulawi yang berbahasa Uma seperti Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu dan Siwongi. Sedangkan di Tuva, sebagian besar penduduknya adalah penghuni baru dari etnis Bugis dan Mandar (45%). Sisanya adalah Toraja, Seko dan Kaili. Sementara orang Sinduru, yang merupakan penghuni pertama, hanya tersisa sedikit (5%), setelah gelombang migrasi ke pantai barat Sulawesi Tengah. 1 Umumnya, matapencaharian mereka adalah petani. Masyarakat Marena menyebut diri sebagai orang Marena atau Kulawi Moma. Sementara orang Sinduru, di Tuva, mengidentifikasi diri sebagai orang Tuva atau orang Sinduru. Menurut Mahori, tokoh adat Tuva, penguasaan atas tanah merupakan otoritas lembaga adat kedua entitas tersebut. Penguasaan mencakup wewenang peruntukan dan pemanfaatan wilayah adat. Di Tuva, misalnya, wewenang peruntukan tanah hingga sekarang masih di bawah wewenang lembaga adat, demikian juga pembagian tanah, baik ke orang Sinduru (Tuva) sendiri maupun pendatang, hingga 1980-an. Namun wewenang lembaga adat untuk membagikan tanah mulai tergerus sejak keputusan pemerintah menetapkan sebagian besar wilayah timur Tuva sebagai Taman Nasional. Lembaga adat kemudian kehilangan otoritasnya di wilayah itu 2 Belakangan, kawasan tersebut menjadi ajang perebutan para pendatang untuk membuka perkebunan kakao. Masalah berkurangnya akses terhadap tanah dimulai dari periode 1970-an. Ketika itu, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penetapan Taman Nasional Lore Lindu, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas persis beririsan dengan wilayah adat. Di Marena, sebagian tanah yang sedang dikerjakan sebagai lahan pertanian dan penggembalaan ternak ditetapkan sebagai daerah penghijauan dinas kehutanan Provinsi Sulteng yang ternyata diperuntukan bagi perkebunan cengkih Perusahaan Daerah Sulteng (PD Sulteng). Wilayah adat pun menyempit. Sebagian masyarakat adat memprotes kebijakan tersebut. Namun, periode 1970 masih sangat dekat dengan trauma pembantaian orang-orang yang dicap PKI pada 1965-1966. Tak jarang tuduhan sebagai PKI menciutkan nyali protes, sehingga mereka pun diam dan bungkam sepanjang era Orde Baru. 3 Intimidasi tidak hanya berupa simbol-simbol aparat koersif seperti polisi dan aparat keamanan lainnya. Di Marena, intimidasi untuk mengambil alih tanah, pertamatama dengan menggunakan adat untuk menjinakkan protes masyarakat. Tokoh adat Marena yang dipercaya masyarakat masa itu bahkan menjadi negosiator penyerahan tanah orang Kulawi Moma ke perkebunan cengkih PD Sulteng. Tokoh adat menjadi salah satu perantara pertama yang membujuk masyarakat untuk mengalihkan hak mereka ke PD Sulteng. 4 Box 1 Sejarah Taman Nasional Lore Lindu Taman Nasional Lore Lindu terletak sekitar 60 kilometer selatan kota Palu dan berada di antara 119°90’ - 120°16’ di sebelah timur dan 1°8’ - 1°3’ di sebelah selatan. Taman Nasional ini meliputi kawasan 217.991.18 ha (sekitar 1.2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km² atau 2.4% dari sisa hutan Sulawesi yakni 90.000 km²) dengan ketinggian bervariasi antara 200 sampai dengan 2.610 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional ini sebagian besar terdiri atas hutan pegunungan dan subpegunungan (±90%) dan sebagian kecil hutan dataran rendah (±10%). Embrio Taman Nasional Lore Lindu dimulai dari penetapan Suaka Margasatwa Lore Kalamanta tahun 1973. Daerah ini berseberangan dengan wilayah adat orang Marena. Tahun 1977, Lore Lindu mendapat dukungan 1 LPA Awam Green, 2001, Dokumen Advokasi, Palu. Mahori, wawancara 28-2-2009, di Tuva, Sulawesi Tengah. 3 Trauma penyiksaan dekil dan pembunuhan massal PKI di Sulawesi Tengah, termasuk daerah Tuva sebagian diulas dalam buku yang diedit Roosa et al. (2004:152-9) 4 Yenny Buha dan Nixen, wawancara 18-2-2009, di Palu; Rince dan Fredy, wawancara 3-3-2009, di Marena. 2 2 bantuan teknis internasional, setelah ditetapkan sebagai Cagar Biosfir oleh UNESCO. Pada tahun 1982, Surat Menteri Pertanian No. 736/Menteri/X/1992 tanggal 14 Oktober 1982 menetapkan luas kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah 231.000 ha. Luas wilayahnya diubah lagi lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 yang menetapkan luas kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah 229.000 ha. Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999, Taman Nasional Lore Lindu dikukuhkan dengan luas kawasan 217.991,18 ha. Luas inilah yang menjadi dasar pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu saat ini. Taman Nasional Lore Lindu secara fisik berbatasan langsung dengan ±61 desa yang tersebar dalam 6 kecamatan di 2 kabupaten yaitu sebagai berkut: • Di dalam kawasan di luar enclave: Katu; di enclave di luar kawasan: (1) lembah Besoa: desa-desa Doda, Bariri, Lempe dan Hanggira serta desa translok Baliura. (2) lembah Lindu: desa-desa Puroo, Langko, Tomado dan Anca. • Di luar Taman Nasional Lore Lindu tapi berbatasan langsung dengan batas fisik Taman Nasional Lore Lindu ada 51 desa dalam 6 Kecamatan yaitu dari timur searah jarum jam: Kec. Lore Utara, Lore Tengah, Lore Selatan (ketiga Kec. ini di Kab Poso); Kec Kulawi, Kec. Sigibiromaru, dan Kec Palolo (ketiga Kec.ini di Kab Donggala). Berdasarkan data resmi sensus penduduk jumlah penduduk dari 6 (enam) wilayah kecamatan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu adalah 68.377 jiwa dari 16.600 KK. 5 Di Tuva, penetapan taman nasional di kawasan sebelah timur yang dulunya dianggap masyarakat Sinduru sebagai wilayah adat Sinduru mengakibatkan banyak kebun warga dan bekas kampung Tuva dikategorikan sebagai Taman Nasional. Menurut undang-undang, daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tidak bisa dialokasikan untuk peruntukan yang lain. Pemanfaatan tanah maupun peruntukan lainnya harus ditertibkan demi mendukung sistem penyanggah kehidupan. Lihat Box 2. Box 2: Pembatasan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Taman Nasional UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 9 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. Pasal 33 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Dalam rangka menegakan pembatasan akses terhadap kawasan taman nasional, Balai Taman Nasional bersama aparat kepolisian menjaga wilayah tersebut dengan ketat, sering kali dengan metode intimidasi. Di Marena, misalnya, aparat pernah membuang tembakan ke udara yang menimbulkan kecemasan bagi warga. 6 5 http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4617&Itemid=1504, download, Jakarta, 12 April 2009 dan www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/lorelindu_NP.htm, akses terakhir 12-4-209 6 Yenny Buha, wawancara 18-2-2009. 3 Dalam perkembangan selanjutnya, semakin banyak tanah yang diambilalih pendatang baik lewat jual beli maupun klaim atas kawasan hutan yang mereka anggap sebagai tanah kosong. 7 Umumnya mereka tidak tinggal di situ, tapi di Palu atau kota lain. Masyarakat hanya tahu bahwa beberapa bidang tanah yang sangat luas dimiliki oleh pejabat atau pengusaha tertentu. Kehilangan tanah membuat masyarakat kesulitan untuk berladang dan mencari padang penggembalaan. Selain itu, di wilayah-wilayah yang sudah diklaim pemerintah atau pejabat pemerintah, lembaga adat tidak lagi berperan mengkontrol dan mengawasi peruntukan dan pemanfaatan wilayah. Di sini, perjumpaan dengan agensi negara, secara tidak langsung, memangkas wilayah kerja dan otoritas lembaga adat. Dia hanya berlaku ke dalam masyarakatnya sendiri, di atas wilayah yang tersisa. Pasca-kejatuhan Orde Baru, perubahan di tingkat nasional juga diikuti oleh pergeseran politik di skala lokal. Isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) menyebar hingga ke kampung-kampung lewat berbagai perantara. NGO adalah satu di antara aktor perantara yang cukup sukses menyebarkan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM di tingkat kampung. Di Marena dan Tuva, sejumlah NGO memfasilitasi lembaga adat dengan informasi-informasi baru mengenai hukum agraria versi negara. LPA Awam Green, misalnya, melalui sejumlah pelatihan menginformasikan peraturan-peraturan yang relevan mendukung apa yang mereka sebut sebagai hak-hak masyarakat adat. Yang paling sering dikutip adalah: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, informasi tersebut dipakai tokoh-tokoh lembaga adat, sering kali untuk memperkuat dan menghidupkan legitimasi kontrol maupun penguasaan tanah yang berbasis klaim adat, terutama ketika mereka berhadapan dengan migran. Selain itu, hukum adat dan hukum negara kerap dipakai secara bersamaan manakala lembaga adat berhadapan dengan klaim institusi negara. Ada semacam rasa percaya diri yang menguat ketika petikan pasal hukum negara diperdengarkan. Menurut para tokoh adat, pasal-pasal hukum negara tersebut mendukung keberadaan masyarakat adat, terutama wilayah adat. 8 Dalam pembicaraan dengan tokoh adat di Marena dan Tuva, pemberlakuan hukum adat diharapkan memperkuat dan menghidupkan otoritas lembaga adat. Misalnya, sejak lama dalam tradisi orang Sinduru dan Kulawi Moma, pembagian tanah selalu dilakukan oleh lembaga adat. Lembaga adat berhak memutuskan boleh atau tidaknya suatu wilayah dimanfaatkan maupun dibagi, baik untuk etnisnya sendiri maupun untuk pendatang. Izin atau restu dari lembaga adat merupakan keharusan. Jika tidak, pelakunya akan dikenakan sanksi 9 Lembaga adat juga berperanan dalam menjaga tetap berlakunya hukum adat lewat sidang-sidang adat. Mekanisme sidang adat, mengeluarkan petuah, perintah atau larangan dan juga memeriksa pelaku pelanggaran adat. Meskipun sanksi yang dijatuhkan ditegakan secara kolektif, namun lembaga adat tetap memantau pelaksanaan hukuman agar tetap berjalan sebagaimana disepakati dalam sidang adat (Prabowo 2006). Dalam hal adanya irisan dengan hukum lain, tokoh-tokoh adat di Marena dan Tuva menguraikan bahwa meskipun belakangan ini hukum negara dirujuk oleh masyarakat adat, rujukan tersebut semata-mata dalam upaya memperkuat pemberlakuan hukum adat. Singkat cerita, lembaga adat berbenah diri dengan menggunakan peluang yang ada, terutama konsep hak masyarakat adat. 7 Seorang Jaksa dari Palu memiliki lahan ratusan hektar di Tuva, demikian juga seorang purnawirawan TNI. Mahori, wawancara 28-2-2009, 8 Nixen, Wawancara 18-2-2009, di Palu. 9 Rince dan Fredy, wawancara 3-3-2009 di Marena; Mahori, Arifin, Roni, wawancara 28-2-2009 di Tuva. 4 Di wilayah konservasi, ada pengakuan Balai Taman Nasional terhadap wilayah adat. Marena mengalami itu lewat kesepakatan bersama dengan balai taman nasional Lore Lindu. Dalam kesepakatan tertulis itu, lembaga adat Marena memiliki wewenang untuk mengkontrol wilayah adatnya, termasuk di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai taman nasional. Menurut tokoh-tokoh lembaga adat, kesepakatan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas masyarakat adat, termasuk peran lembaga adat Marena. 10 Namun orang Sinduru tidak mengalami perubahan seperti itu. Meski difasilitasi NGO Konservasi yang dikenal dekat dengan pihak Balai Taman Nasional, masih banyak orang Sinduru yang bolak-balik dipanggil pihak Balai Taman Nasional karena diduga melakukan perambahan kawasan konservasi. Padahal, dalam peta wilayah adat, kawasan tersebut juga merupakan wilayah adat yang harus dijaga oleh lembaga adat Sinduru. Sejak lama, adat memang telah bergeser. Larangan menjual tanah dilanggar berkali-kali bahkan sering kali dipicu oleh para tokoh adat. Kenyataannya, saat ini, sebagian besar tanah dikuasai secara individu. Di Tuva, tanah-tanah tersebut sering kali diperjualbelikan dengan migran yang datang secara bergelombang pada penghujung 1990-an pasca-melonjaknya harga komoditi kakao di pasar internasional (Li 2007:109-11). Para migran segera merebut status ekonomi kelas menengah. Mereka memiliki kios kecil, rumah mewah, kendaraan bermotor, TV dengan antena parabola, sementara tetangganya, penduduk asli orang Sinduru, hidup dalam keterpurukan (Sitorus 2002). Dalam penyelesaian kasus-kasus adat, hampir tidak pernah terjadi sengketa atas jual beli tanah. Lembaga adat goyah menegakkan hukum adat atas mekanisme jualbeli yang secara masif dikembangkan migran dan seterusnya menggoda orang Sinduru untuk terlibat dalam mekanisme itu dan untuk meramaikan pasar kakao. Pasca-gelombang gerakan masyarakat adat, dukungan dan penolakan terhadap peran lembaga adat senantiasa datang silih berganti atau secara bersamaan. Dalam banyak kasus yang akan diperlihatkan studi ini, program NGO, perilaku pendatang, kehadiran taman nasional dan birokrat taman nasional, polisi hutan, camat dan pemerintah desa saling tumpang tindih bersamaan maupun silih berganti, mempengaruhi posisi dan peran lembaga adat. NGO, misalnya, menggerakan programnya dengan misi memfungsikan lembaga adat. Tapi pada saat yang bersamaan program-program tersebut juga melucuti peran lembaga adat melalui skema yang mengalihkan sebagian otoritas lembaga adat ke lembaga-lembaga bentukan baru. Demikian halnya dengan pendatang. Dalam satu kasus mereka tunduk pada lembaga adat tapi dalam kasus lain, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan penjatuhan sanksi adat, mereka sama sekali tidak menghiraukan bahkan menyerang balik lembaga adat. Konsep Masyarakat Adat Jika diperiksa ke belakang, rujukan masyrakat adat yang dipakai NGO agak lepas dari konteks historis masyarakat adat versi kolonial Belanda 11 Di era kolonial istilah yang kerap dipakai adalah rechtsgemeenschap atau volksgemeenschap yang, kalau tidak dapat dikatakan sama, paling tidak mendekati pengertian Gemeinschaft dalam bahasa Jerman yang digunakan oleh sosiolog Jerman, Ferdinand Tönnies. Istilah Gemeinschaft yang digunakan Tönnies ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah community. Konsep Gemeinschaft atau community 10 Fredy dan Rince, wawancara 3-3-2009, di Marena, Sulawesi Tengah. Belanda menggunakan istilah pribumi dan masyarakat hukum adat untuk menunjuk komunitas yang memiliki hukum sendiri, di luar hukum kolonial Belanda. Studi-studi ini dipelopori oleh Van Vollenhoven (1987 [1928]). 11 5 menunjukkan suatu ikatan sosial primer yang hubungan antara anggotanya akrab, bersifat pribadi dan eksklusif (Zakaria 2000:43-44). Para pemikir masyarakat hukum adat era kolonial memberi ciri masyarakat hukum adat yang lebih antropologis daripada politik. F.D Hollemann, misalnya, mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis-religius, komunal, konkret dan kontan. Sifat magis diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sifat komunal berkaitan dengan pemikiran bahwa dalam masyarakat adat anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Konkret berkaitan dengan corak hubungan yang serba jelas dan nyata, sehingga setiap hubungan hukum yang terjadi tidak dilakukan secara samar-samar atau diam-diam. Kontan mengandung arti kesertamertaan, terutama dalam pemenuhan prestasi (Holleman, dalam: Soemadiningrat 2002:29-34). Ter Haar, seorang pemikir hukum adat era Belanda juga memberikan formulasi mengenai masyarakat adat, yakni persekutuan hukum masyarakat yang memiliki kekuasaan sendiri, yang percaya bahwa masyarakat tersebut terjadi karena alam atau kekuasaan gaib, memiliki kekayaan sendiri dan tidak seorang pun anggotanya memiliki pikiran untuk membubarkan persekutuan tersebut. Tetapi, anggotanya bisa keluar dari persekutuan tersebut, namun hal ini tergantung karakteristik masing-masing daerah (Ter Haar 2001:6-8). Berbeda halnya dengan NGO, yang menggunakan istilah masyarakat adat dalam kaitannya dengan perkembangan tuntutan masyarakat adat di tingkat internasional, menempatkan masyarakat adat sebagai komunitas marginal yang diakui secara historis memiliki landasan klaim hak yang bersifat khusus tapi dalam perkembangannya mengalami ketidakadilan struktural akibat penerapan kebijakan pemerintah maupun dampak operasi korporasi multi-nasional di wilayah mereka. Menurut Anaya, secara historis indigenous bukan hanya orang (people) tapi terlebih sebagai suatu kolektif (peoples). Di situ, berbagai ketidakadilan yang mereka hadapi, dialami tidak hanya sebagai pengalaman individual tapi terutama sebagai suatu pengalaman kolektif. 12 Selanjutnya, seorang ilmuwan hukum Benedict Kingsbury, mengusulkan definisi yang cair dan fleksibel terhadap masyarakat adat mengingat kemajemukan yang mereka miliki baik dalam komunitas maupun antar-komunitas. Kingsbury mengajukan empat syarat esensial cakupan masyarakat adat, yakni: 1. Identifikasi diri sebagai grup etnik yang berbeda; 2. Pengalaman sejarah pernah dan terus merasakan ketidakadilan, dipecah belah hingga berantakan, dipindahkan dari kampung halaman dan dieksploitasi; 3. Memiliki hubungan yang lama dengan wilayah; 4. Harapan untuk meneruskan identitas yang berbeda (Corntassel, dalam: Erni (ed) 2008:56-7). Ketidakadilan yang digarisbawahi Kingsbury, dalam gerakan masyarakat adat yang dipelopori oleh NGO, sering dikaitkan dengan akses terhadap tanah. Dalam berbagai forum masyarakat adat, hubungan antara masyarakat adat dengan tanah senantiasai digarisbawahi sekaligus menempatkan tanah sebagai salah satu prioritas paling utama yang diperjuangkan masyarakat adat dewasa ini. IWGIA (International Working Group for Indigenous Affairs), misalnya, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan mengenai situasi ketidakadilan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Dalam laporan tahun 2008, IWGIA 12 Lihat definisi Cobo, http://www.iwgia.org/sw310.asp (diunduh pada 4-2009). Lihat juga Anaya (1996:77). 6 memaparkan sejarah ketidakadilan tersebut dengan memakai kasus Papua sebagai salah satu contoh. IWGIA menulis sebagai berikut: Pemerintah Indonesia mengeruk sumber daya alam Papua Barat dalam jumlah yang sangat besar. Hutannya dibabat dan kandungan mineralnya dikeruk tanpa konsultasi dengan komunitas adat, dan tanpa sedikit pun manfaat balik bagi komunitas adat itu. Dengan program transmigrasi yang disponsori negara sejak 1970-an, pemerintah Indonesia telah menempatkan lebih dari 10.000 keluarga setiap tahun yang didatangkan dari Jawa dan bagian-bagian lain Indonesia. Selain itu, ada juga orang yang berpindah atas inisiatif mereka sendiri ke Papua Barat, yang jumlahnya tak terlacak. Diperkirakan bahwa lebih dari 750.000 orang dari bagian lain Indonesia telah bermukim di Papua Barat, yang perbandingannya sekarang adalah lebih dari 30% dari total 2,2 juta penduduk di Papua Barat. Ada kekhawatiran yang besar bahwa perlahan-lahan orang Papua akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri (IWGIA 2006:266) Sedikit menengok ke belakang, perjuangan kelompok pendukung hak masyarakat adat di tingkat internasional dimulai dari hak ekonomi, sosial budaya lewat berbagai advokasi NGO dan organisasi rakyat di Amerika Latin yang mencetuskan Konvensi ILO No. 169/1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Upaya lobi dan tekanan terus berlanjut ke berbagai hak lain, termasuk hak sipil dan politik. Pada 2007, gerakan indigenous peoples dari berbagai belahan dunia akhirnya berhasil mendorong Majelis Umum PBB mengeluarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), tanggal 12 September tahun 2007. Persoalan ketidakadilan juga menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi terbentuknya UNDRIP. Dalam pembukaan deklarasi disebutkan bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingannya. 13 Di Indonesia, gerakan NGO untuk mendukung hak masyarakat adat secara teroganisir tampak dalam tercetusnya JAPHAMA (Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat) pada 1993 sebagai respons atas permasalahan ketidakadilan struktural yang dihadapi kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat adat. Istilah tersebut juga merupakan respons atas kategori masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan yang kerap digunakan pemerintah dalam kebijakan maupun program. Istilah-istilah itu merupakan “stempel” yang menurut NGO dan pengalaman sejumlah komunitas, sarat dengan tuduhan diskriminatif dan melecehkan kelompok masyarakat adat. Masyarakat terasing, misalnya, bisa dimaknai sebagai masyarakat yang tidak mengenal peradaban lain, terkunci di suatu tempat yang tidak dikenal. Demikian halnya dengan istilah peladang liar, bisa diterjemahkan sebagai seolah-olah masyarakat adat tidak memiliki aturan bercocok tanam sehingga dikerjakan secara liar tanpa kontrol. 14 Selanjutnya, melihat ada banyak kemiripan antara konsep dan pengalaman masyarakat adat dengan konsep indigenous peoples dalam kerangka hukum internasional maka masyarakat adat kerap dipadankan dengan indigenous peoples (Moniaga 2003:1). 15 Sehingga kerangka hak 13 Pembukaan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, diadopsi Majelis Umum PBB, 12 September 2007. 14 Perdebatan dan kritik atas penggunaan istilah-istilah ini terjadi dalam kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 17-22 Maret 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. 15 Diakses dari www.huma.or.id, 10-1-2009. 7 dalam konsep indigenous peoples digunakan juga dalam tuntutan hak dari masyarakat adat, misalnya hak atas identitas kolektif, tanah kolektif, sistem nilai kolektif dan seterusnya. Gelombang perubahan sebagai efek lanjutan kejatuhan Soeharto juga merembet ke perjuangan NGO dan sejumlah masyarakat adat. Pada 1999, JAPHAMA mencetuskan sebuah organisasi masyarakat adat, yang disebut AMAN. AMAN menyepakati bahwa masyarakat adat “adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan) (Moniaga 2002). Konsep masyarakat adat versi AMAN kerap dirujuk tokoh-tokoh adat, terutama yang memiliki jaringan dengan NGO atau dengan AMAN. Fredy, seorang pendeta di Marena misalnya, menggunakan istilah bermartabat secara budaya, berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi yang merupakan konsep AMAN, dalam merumuskan gerakan masyarakat adat di Marena. Ketidakadilan penguasaan tanah dan ancaman-ancaman baru pengambilalihan tanah, dijawab dengan konsep masyarakat adat yang menurut para tokoh adat, seperti Fredy di Marena, Arifin di Tuva, harus diakui dan dilindungi. Istilah masyarakat adat dan kekhususan haknya, sebetulnya menimbulkan sejumlah kritik tajam, antara lain menyangkut kerumitan definisi dan ukuran-ukurannya secara normatif maupun konsekuensi sosial politik dari kekhususan tersebut. Namun gerakan NGO, pemerintah, Organisasi Internasional dan para ilmuwan lainnya yang umumnya menggunakan argumen berbasis hak, tetap mendorong hak masyarakat adat, sehingga lambat laun terserap dalam kerangka hukum (Bedner dan Van Huis 2008). Dalam sejumlah hukum nasional maupun internasional, masyarakat adat diwarisi keistimewaan untuk mendapat keutamaan dalam sejumlah hak, terutama hak atas tanah, wilayah dan hukum adat. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak masyarakat adat atas tanah, khususnya dalam Pasal 6, yaitu sebagai berikut: 1) 2) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Selain itu, dalam konstitusi pasca-amendemen, keistimewaan masyarakta adat juga diakui. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merumuskan sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Meski demikian, secara historis adat dalam hukum nasional tidak terdefinisikan. Henley dan Davidson memaparkan adat, sebagaimana halnya dengan konsep-konsep identitas lainnya, mempunyai banyak arti. Dalam konteks modern, adat cenderung dipahami sebagai institusi tertentu yang diwariskan dalam tradisi-tradisi lokal dan dalam konteks Indonesia wacananya berkisar antara sejarah, tanah dan hukum. Sebagian lagi bersentuhan dengan ideologi politik yang samar-samar tetapi juga daya tarik secara nasional yang mengidentifikasikan adat sebagai otensitas, komunitas, keteraturan dan keadilan (Davidson dan Henley 2007:19). Pencari Keadilan: Masyarakat Adat Tuva dan Marena 8 Gelombang pengakuan masyarakat adat dan introduksi hak-hak atas tanah yang diperkenalkan oleh sejumlah NGO diakui tokoh adat Marena dan Tuva turut mendorong upaya orang Marena dan Tuva untuk mengembalikan tanah yang telah diambil-alih pemerintah maupun pengusaha. Dengan merujuk pada sejumlah peraturan nasional maupun hukum Internasional, mereka menyebut syarat-syarat masyarakat adat yang mirip dengan karakter mereka sebagai suatu komunitas adat. Mahori dan Rince, berturut-turut ketua lembaga adat Tuva dan tokoh adat Marena, memperkenalkan karakter adat yang mereka miliki, antara lain memiliki sejarah, hukum, wilayah dan komunitasnya. Karakter ini kurang lebih mirip dengan ciri atau keunikan masyarakat adat yang diperkenalkan oleh NGO lewat berbagai pelatihan, diskusi kampung maupun penelitian advokasi. Karakter dikutip dari referensi gerakan masyarakat adat di tingkat internasional maupun nasional (ICRAF et al. 2003) Di sini, orang Marena dan Tuva kemudian mengklaim diri sebagai masyarakat adat. Salah satu argumen yang kerap dihadirkan adalah, sebagai penghuni pertama di wilayah tersebut, merekalah yang layak disebut sebagai masyarakat adat. Penguasaan berbasis historis ini kurang lebih mirip dengan pemikiran Anaya, Kingsbury maupun Cobo yang memberi kekuatan ilmiah pada konsep ini di skala internasional. Aturan hukum yang dinilai melindungi hak masyarakat adat sering kali dikutip dan diambil oleh sejumlah tokoh adat untuk menegaskan ke birokrat daerah bahwa hak mereka pun dilindungi dan diakui oleh peraturan Negara. Menurut Nixen, tokoh adat Marena, informasi keberadaan peraturan tersebut diperoleh dari sejumlah NGO, misalnya, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UndangUndang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Klaim orang Sinduru dan Tuva pada gilirannya berimplikasi pada penguasaan tanah, penentuan sejarah wilayah dan implementasi hukum adat. Jika mengikuti konsep hukum adat maka seluruh tanah di dua kawasan tersebut merupakan milik orang Sinduru dan orang Kulawi Moma. Apabila suatu kawasan hendak dibuka, di sana telah tersedia aturan tentang akses terhadap tanah. Sejumlah prosedur tercantum secara lisan dalam warisan ingatan tokoh-tokoh lembaga adat. Karena itu, sejarah penguasaan wilayah menjadi kunci keabsahan klaim. Sebagaimana dipaparkan Mahori, kehadiran nenek moyang mereka sebagai pendahulu atau penghuni pertama juga sekaligus bermakna memiliki kawasan tersebut. Dalam hal ini, hanya dengan merujuk sejarah penguasaan pertama kali, klaim sebagai masyarakat adat relevan untuk dihubungkan dengan klaim atas wilayah. Wilayah dan sejarah dijaga oleh hukum adat untuk meneruskan dan merawat relasi yang terdapat di dalamnya. Artinya, dalam wilayah adat diharapkan tetap berlaku hukum-hukum adat. Dalam praktiknya, sejumlah kerangka konseptual dan normatif tentang masyarakat adat terartikulasi dalam kategori keistimewaan unsur-unsur atau komponen masyarakat adat misalnya sejarah asal muasal, kearifan ekologis, penguasaan wilayah dan hukum adat. Di Sulawesi Tengah, keistimewaan tersebut, antara lain dipromosikan oleh NGO, seperti Bantaya, LPA Awam Green, Yayasan Merah Putih, Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah. Peran NGO lewat penyebaran informasi dan pengetahuan baru juga mendorong restrukturisasi adat. Para tokoh adat sering kali menggunakan konsep hak asasi manusia maupun representasi stakeholders sebagai argumentasi untuk membentuk struktur baru. Di Marena misalnya, muncul anggota lembaga adat yang mewakili perempuan dan pemuda adat. Isu perempuan sering kali dibawa oleh NGO yang bergerak di isu tersebut dan mendorong 9 pemerintah maupun NGO lainnya atau langsung melakukan intervensi ke lembaga-lembaga adat untuk menempatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. 16 Namun, ciri masyarakat adat yang kerap menonjol di Marena dan Tuva berkaitan erat dengan posisinya di pinggiran kawasan konservasi, yakni ciri kearifan ekologis yang menurut tokoh-tokoh adat telah diterapkan dari generasi ke generasi. Konsep ini menekankan kapasitas masyarakat adat menjaga stok sumber daya alam dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. 17 Konsep ini didukung dan dipromosikan oleh banyak NGO, sering kali dengan cara dipertandingkan dengan konsep konservasi taman nasional versi negara atau versi lembaga konservasi internasional, seperti TNC, yang dianggap sebagai pinjaman dari konsep Barat yang tidak membumi bahkan cenderung mengabaikan masyarakat adat. Dalam konsep kearifan ekologis tersebut, kerangka hukum adat dijadikan rujukan, bahkan didokumentasikan oleh masyarakatnya dengan difasilitasi oleh sejumlah NGO. Dokumentasi tersebut mencatat jenis hukum sumber daya alam (terutama tanah, sungai, mata air, hutan), larangan, hingga sanksi bila hukum tersebut dilanggar. Informasi konseptual maupun kerangka normatif yang intensif mengenai hak masyarakat adat pada giliran berikutnya menjadi rujukan bagi masyarakat adat sendiri ketika mereka bertutur tentang dirinya sendiri. Setidaknya itulah yang tersampaikan ketika Arifin dan Rince, berturutturut adalah tokoh adat Sinduru dan tokoh adat Marena, memaparkan keberadaan masyarakat adat secara konseptual, persis seperti kerangka yang diperkenalkan oleh sejumlah NGO, seperti Awam Green dan Bantaya. 18 Arifin diajak Awam Green menjadi salah seorang periset yang menggali data mengenai mekanisme penyelesaian adat terhadap konflik tenurial di Tuva. Laporan riset memang tidak langsung berhubungan dengan penyelesaian sengketa tetapi lebih cenderung memaparkan seluk-beluk orang Sinduru dalam berbagai aspek, yakni sejarah asalmuasal, lembaga adat, wilayah adat, hukum adat dan kearifan lokalnya dalam kaitannya dengan upaya menjaga keberlanjutan hutan. Singkatnya, skema laporan ini persis seperti panduan yang diperkenalkan oleh LSM yang mempromosikan eksistensi masyarakat adat. Di sisi lain, Arifin dan tokoh masyarakat adat lainnya berulang kali menegaskan bahwa motif mereka menguatkan adat dan perannya antara lain agar hukum adat ditegakkan secara efektif, lembaga adat bisa bekerja dengan baik dan wilayah adat dipertahankan. 19 Motif tersebut 16 Dalam sejarah lembaga adat di Marena, beberapa kali perempuan pernah mengisi struktur adat. Menurut tokoh adat, pengalaman itu tidak membuat mereka merasa asing dengan kehadiran perempuan dalam struktur adat. Modal sosial tersebut dipikirkan kembali setelah informasi dan perkembangan baru diterima dan direfleksikan dalam keputusan lembaga adat. Wawancara degan Nixen, 18-2-2009. 17 Seorang aktivis NGO misalnya berulang-ulang menggarisbawahi cara hidup masyarakat adat yang memperlihatkan hubungan yang saling mendukung antara manusia dengan lingkungan. Cara berpikir ini sebetulnya sangat kuat dipengaruhi oleh kemunculan isu lingkungan hidup dalam wacana Internasional sebagai protes atas cara pembangunan top-down yang eksploitatif. Gerakan pro-lingkungan di berbagai negara sejak era 1960-an melahirkan banyak konsep antara lain konsep hubungan yang setara dengan alam yang segera ditemukan dalam pola relasi masyarakat tradisional dengan lingkungannya. Cara pemenuhan kebutuhan mereka yang subsisten dengan meramu dan mengumpulkan makanan dari alam dianggap sebagai salah satu wudud pola relasi yang menjamin sustainability sumber daya, sehingga harus dipromosikan sebagai bentuk kearifan (Durning dalam Brown 1995:204-61). 18 Beberapa NGO memang mengambil sikap bahwa konsep tentang masyarakat adat yang mereka bawa dikemas secara hati-hati agar pada tingkat komunitas menjadi tawaran dan bukan pilihan yang harus ditaati oleh para tokoh adat. Namun bagi tokoh-tokoh adat, sebagaimana diterangkan Nixen, informasi-informasi tersebut adalah rujukan baru yang dipakai untuk memperkuat posisi mereka. 19 Wawancara Arifin Panjaitan dan Roni, bekas anggota Lembaga Adat Sinduru di Tuva, 28-2-2009. 10 sering kali dibarengi dengan contoh pelanggaran hukum adat dan peran lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut dengan logika hukum adat yang tegas dan konsisten. Akses Terhadap Tanah: Sebuah Persoalan Pasca-pengambilalihan tanah oleh PD Sulteng, data statistik menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah di kedua wilayah. Di Marena, beberapa fakta, antara lain, dari 80 kepala keluarga, 14 keluarga menguasai tanah 0,5 ha dengan tanggungan rata-rata 2-4 jiwa, 12 keluarga menguasai masing-masing 1 ha dengan tanggungan 4-5 jiwa. Selain itu, terdapat 15 keluarga yang tidak memiliki tanah, namun mereka rata-rata memiliki tanggungan 2-4 orang anggota keluarga. Terdapat 1 KK yang menguasai tanah hanya 0,25 ha tapi memiliki tanggungan 6 orang. Jika dimasukkan dalam prosentase, rata-rata per orang menguasai tanah di bawah 0,5 ha. Penguasaan ini dikelola secara tradisional sehingga jumlah penghasilannya pun terbatas, sering kali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, anggota keluarga tersebut minta restu tetangga, sesama warga Marena agar dipinjami kebun untuk tanaman berumur pendek seperti jagung, ubi dan berbagai jenis tanaman pangan untuk keperluan sendiri. Statistik serupa tidak jauh berbeda dengan di Tuva. Setelah dijepit oleh taman nasional, sebagian tanah di wilayah ini juga beralih ke tangan para pejabat dan pengusaha dari kota. Dari 19,22 km² luas wilayah Tuva, 10,08 km² merupakan hak milik 6 orang dan 1 perusahaan atau 54% dari wilayah Tuva. Mereka umumnya pendatang dari wilayah lain. Seorang Jaksa di Palu (Amir Pakude) memiliki tanah seluas 104 ha yang diperoleh dengan cara menyerobot wilayah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan sejak lama oleh orang Sinduru. Sejumlah pejabat, polisi kehutanan, aparat militer dan pengusaha juga menguasai tanah di Tuva dalam jumlah yang luas, antara 8-70 ha. Mereka berargumen, kawasan-kawasan tersebut merupakan tanah kosong yang bisa diajukan hak milik sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Selain itu, CV Satria Abadi dan Koperasi Unit Desa Singgani, berbekal SK Bupati No. 188.45/0307/BAG.PEM dan No. 188.4/0310/BAG.PEM tanggal 11 Mei 1994 tentang mengelola tanah Negara, bebas juga beroperasi di Tuva. Seharusnya, izin lokasi tidak sampai ke wilayah Tuva, tapi praktiknya KUD tersebut masuk ke Tuva untuk melakukan penebangan kayu. Wilayah itu, menurut hukum adat Sinduru, merupakan bagian dari wilayah adat mereka. Menurut Konstruksi UU No. 56 Prp 1960, komposisi luas tanah pertanian adalah sebagai berikut: Hak Penguasaan tanah dalam bentuk: Hak milik, Sewa, Hak Pakai, HGU, Bagi Hasil Hak milik per keluarga Luas tanah • 20 hektar • Mengingat keadaan daerah, bisa ditambah 5 ha Diusahakan pemerintah minimum 2 ha Peruntukan • Sawah atau tanah kering • Sawah dan tanah kering Tanah pertanian Pasal 1 ayat (1) & (2) 8 Namun hampir semua komposisi ini sama sekali tidak terwujud di Tuva dan Marena. Yang terwujud justru pelanggaran atas undang-undang ini yakni penguasaan tanah hak milik pertanian melampaui 20 hektar oleh pengusaha, politisi dan pejabat dari Palu (LPA Awam Green 2001). 11 Sejak lama, orang Sinduru dan Kulawi Moma resah dengan persoalan tersebut. Pascakejatuhan Soeharto, mereka mulai melakukan lobi dan negosiasi dengan pemerintah maupun pengusaha dengan menggarisbawahi status mereka sebagai masyarakat adat. Konsep itu dengan segala kekhususannya merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam kosa kata Sinduru maupun Marena. Sehari-hari, mereka menyebut dirinya orang Sinduru atau orang Kulawi Moma. Penyebutan tersebut tidak lebih dari identifikasi diri untuk memastikan dari mana mereka berasal, dengan membedakan diri dari Bugis, Sarudu, Jawa maupun suku lain di sekitar mereka, tanpa suatu pesan dan maksud politik seperti keistimewaan yang tersedia bagi istilah masyarakat adat. Namun, pasca-1998 istilah masyarakat adat menyeruak masuk ke kedua komunitas ini, terutama oleh peran NGO. Berbagai NGO yang mendukung gerakan masyarakat adat menyebut istilah ini dan memaparkan acuan kerangka konseptualnya yang diterima oleh hukum nasional dan tercantum dalam hukum internasional. Istilah ini banyak mengubah makna dan cakupan penamaan sebagai Sinduru dan Kulawi Moma; bukan lagi sekadar panggilan atau penamaan diri untuk membedakan diri dari etnis lain tapi segera menjadi benefit. Singkatnya, istilah tersebut membawa banyak konsekuensi baru bagi orang Kulawi dan Sinduru, terutama dalam kaitannya dengan tanah. Peran Penengah Konflik Sebagai komunitas di tepi kawasan konservasi, relasi Sinduru dan Marena dengan kawasan hutan sudah berlangsung lama, tapi awal 1990-an juga menjadi perhatian berbagai organisasi lain. Kehadiran program TNC tahun 1992 dan beberapa LSM lain menandai silih berganti informasi yang diterima masyarakat adat dalam isu konservasi. Beberapa NGO seperti Bantaya, Yayasan Merah Putih, Yayasan Tanah Merdeka dan LPA Awam Green cenderung menggunakan perspektif hak masyarakat atas otonominya sendiri untuk mendorong masyarakat dari situasi kurang melek (unperceived injurious experience, unPIE) menjadi menyadari (perceived injurious experience, PIE) kegagalan kebijakan pemerintah, ketidakadilan relasi sosial-politik, dan dampak-dampak langsung yang mereka hadapi akibat konservasi dan kebijakan peruntukan kawasan lainnya. 20 Berbasis otonomi tersebut, kelompok NGO ini percaya bahwa masyarakat adat sanggup mengolah dan melestarikan kawasannya, tanpa harus diceramahi oleh konsep konservasi yang berasal dari luar. Sebagian di antaranya mengkategorikan konservasi ala TNC sebagai konservasi fasis karena semata-mata mengedepankan penghargaan atas hak hewan dan tumbuhan, sementara keberadaan manusia hampir terlupakan. 21 Dalam implementasi konsep pun, dua kubu ini berbeda satu sama lain. LPA Awam Green percaya bahwa konsep konservasi harus berasal dari komunitas sendiri dan didukung serta digerakan oleh lembaga adat. Sementara TNC menggunakan aturan negara sebagai rujukan utama dan menempatkan komunitas adat serta komunitas lainnya dalam posisi yang sama. Keistimewaan nilai tradisional suatu komunitas, dalam pandangan TNC, diberlakukan sejauh mendukung konservasi. Program TNC tidak lepas dari pengaruh perkembangan konsep konservasi di tingkat internasional. Sebelum 1970, perspektif koservasi sangat dikuasai oleh paradigma biosphere reserve yang menempatkan tujuan konservasi pertama-tama sebagai upaya perlindungan 20 Konsep unPIE dan PIE dapat dilihat dalam Felstiner et al. (1980/1981:633) Acciaioli 2006 http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001815/00/Acciaioli_Greg.pdf, diunduh pada 17-42009; lihat juga Fakih dalam Dietz (1998:x-xi). 21 12 lingkungan hidup non-manusia. Selain itu, pengelolaannya pun menjadi monopoli pemerintah dan sejumlah organisasi konservasi internasional, termasuk TNC. Dekade 1970-an kemudian ditandai dengan berbagai tuntutan di belahan dunia yang mendorong agar paradigma dan pengelolaan konservasi seharusnya melibatkan komunitas di dalam dan sekitar kawasan konservasi, terutama masyarakat adat. TNC, sebagai salah satu pionir terkemuka dalam mendukung kawasan taman nasional, juga tidak luput dari tuntutan tersebut. Dia mengembangkan konsep eco-region dan memperlihatkan komitmen untuk co-management atau pengelolaan kolaboratif melalui kerja bersama partner lokal, termasuk masyarakat adat. Meski tetap mengembangkan kerja sama dengan masyarakat adat namun program TNC tetap mendukung keberadaan zona inti taman nasional sebagai wilayah yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh manusia. Dalam hal ini, jendela paradigma biosphere reserve sebetulnya masih dominan dalam perspektif konservasi TNC. Di Indonesia, TNC bekerja sama dengan Dirjen PHKA Departemen Kehutanan untuk mendorong semakin berkembangnya kawasan konservasi. Program inti mereka adalah pengembangan kawasan konservasi yang didukung oleh dana dari berbagai perusahaan internasional, seperti General Motors, American Electric Power, Caterpillar. 22 Kedekatan dengan perusahaan-perusahaan ini acap kali mendapat sindiran dan kritik tajam dari sejumlah NGO. Seorang pengkritik, Keith, dalam website TNC bahkan menulis The Nature Conservancy: Partnering with Poisoners. 23 Kritik ini kurang lebih mirip dengan kritik sejumlah aktivis di Indonesia, termasuk di wilayah kerja TNC, Taman Nasional Lore Lindu (lih. Acciaoli 2006). Di Taman Nasional Lore Lindu, setelah inisiatif ko-manajemen konservasi dituangkan oleh berbagai NGO, TNC mengembangkan konsep Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM). Konsep ini tidak menempatkan lembaga masyarakat adat sebagai satu-satunya pilihan partner pengelolaan konservasi tapi hanya menyebut komunitas pinggiran kawasan konservasi sebagai mitra pelaksanaan program. Artinya, dia tidak memperlakukan masyarakat adat dan pendatang secara berbeda. Sehingga lembaga konservasi hasil kesepakatan tersebut ditempatkan di tingkat desa, bukan di lembaga adat. Namun, meski mempromosikan kesamaan, program KKM ini justru menggunakan konsep yang biasa dipakai mendukung keberadaan masyarakat adat. Misalnya, penelusuran sejarah desa dan kearifan lokal sebagai dua konsep yang kerap digunakan para pembela hak masyarakat adat. NGO pendukung masyarakat adat pun, meski sadar membela hak masyarakat adat, juga melihat pentingnya penghargaan terhadap hak kelompok lain, seperti perempuan dan etnis pendatang. Namun barisan NGO ini cenderung mengedepankan promosi hak masyarakat adat tanpa kritik, karena menurut mereka fakta di lapangan hak-hak tersebut dilanggar secara telanjang oleh pemerintah maupun pemilik modal. Bagi mereka, di tengah perjuangan memulihkan hak, agak kontraproduktif jika secara bersamaan dialamatkan juga kritik atas hak tersebut. 24 Sebagian NGO ini memiliki program khusus yang didanai sejumlah donor. Mereka bekerja mengikuti target output yang direncanakan, tapi juga sering kali dimodifikasi sedemikian rupa agar fleksibel mengikuti situasi di lapangan. Bantaya, misalnya, mensyaratkan keterlibatan anggota masyarakat adat dalam aktivitas-aktivitasnya. Dalam istilah mereka, tidak dikenal konsep masyarakat dampingan atau wilayah kerja tetapi menggunakan istilah rekan kerja. Istilah “rekan” lebih menampilkan makna egaliter daripada “masyarakat dampingan” yang bisa 22 http://www.cbd.int/financial/businessfunding.shtml, Jakarta, April 2009. http://thesietch.org/mysietch/keith/2008/04/19/the-nature-conservancy-partnering-with-poisoners/ 24 Sahrun, wawancara 18-2-2009, di Palu. 23 13 dimaknai top-down. 25 Selain itu, beberapa aktivitas mereka tidak berbasis program yang terencana, tapi merespons kasus yang terjadi di lapangan. Pengalaman LPA Awam Green dalam kasus illegal logging di Tuva dan reklaiming di Marena, sama sekali tidak tercantum dalam program yang didanai. Perlawanan: Mengembalikan Tanah Adat Tokoh adat Marena, Rince dan Nixen, mengungkapkan bahwa rasa tidak adil mengenai penguasaan tanah yang timpang sebetulnya sudah berlangsung sejak lama, namun tuntutan tersebut tenggelam dalam gerutuan sehari-hari dan tidak terungkap ke lembaga-lembaga pemerintah karena takut diintimidasi aparat dan dikategorikan sebagai PKI, sebuah cap mematikan terutama semasa Orde Baru bagi siapa saja yang kritis dan progresif menentang penguasa dan kroninya. Sekarang ini, setelah mendapat banyak informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber, terutama NGO, semua peristiwa pengambilan tanah tersebut mereka kategorikan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. 26 Menurut mereka, ada beberapa tingkat ketidakadilan yang mereka alami: Pertama, kebijakan pemerintah. Ada dua kebijakan pemerintah yang langsung berpengaruh terhadap akses atas tanah, yakni penetapan peruntukan kawasan konservasi dan peruntukan kawasan produksi. Penetapan Taman Nasional Lore Lindu yang dimulai tahun 1970an, memiliki implikasi pembatasan akses atas sumber daya alam secara langsung bagi masyarakat adat di Tuva dan Marena. Menurut orang Marena dan Tuva, proses dan substansi penetapan kawasan taman nasional sangat tertutup. Warga selanjutnya diminta untuk tidak masuk ke dalam kawasan tapi pada awalnya tidak begitu jelas mengapa ada larangan (lihat Box 3). Kepatuhan akhirnya terjadi melalui sejumlah ancaman dan intimidasi dari pihak taman nasional. Box 3: Proses Penetapan Tata Batas Taman Nasional Ketika tata batas Taman Nasional Lore Lindu berupa patok-patok semen dibuat oleh Dinas Kehutanan setempat, mereka mempekerjakan warga setempat untuk mengangkut patok-patok tersebut agar ditanam mengikuti instruksi petugas dari Dinas Kehutanan. Ami dan Mahori, orang Sinduru masih mengalami langsung proses itu. Menurut mereka, tidak ada informasi mengenai fungsi patok-patok tersebut. Masyarakat diberi upah untuk memikul patok tersebut. Sebagian patok tersebut ditancapkan begitu saja di kebun orang karena para pekerja tidak sanggup memikul patok dalam jarak yang jauh dan medan yang berat. Alhasil, di kemudian hari patok-patok tersebut menjadi acuan bagi petugas Taman Nasional untuk memastikan tata batas kawasan, tapi juga sekaligus terbatasnya bahkan terputusnya akses para pemilik kebun atas kebunnya sendiri. Selain Taman Nasional, bentuk kebijakan negara yang lain adalah menggunakan argumen konservasi untuk menutupi bisnis terselubung sejumlah aparat pemerintah daerah. Kasus Perkebunan Cengkih Pronvinsi Sulawesi Tengah menjadi contoh untuk kebijakan ini. Lihat box 4. Box 4: Penghijauan untuk Kebun Cengkih Rince, tokoh adat Marena, mengalami langsung peristiwa pengambilalihan tanahnya pada tahun 1970. Tanah yang 25 26 Hedar Laudjeng, wawancara 12-2-2008 di Palu. Nixen, wawancara 18-2-2009 di Palu, Rince, wawancara 3-3-2009. 14 dibuka generasi pertama orang Marena tahun 1932, diambilalih Dinas Kehutanan sebagai kawasan penghijauan. Total luas tanah yang diambil adalah 125 ha. Sebetulnya, total tanah yang diambilalih untuk proyek perkebunan cengkih adalah 625 ha. Sebagian kawasan lainnya diambil dari tanah warga di Salua (50 ha), waTuvalih (325 ha), Makuhi (100 ha). 27 Akibat program tersebut, masyarakat dilarang untuk berkebun dan membuka tempat penggembalaan ternak di wilayah itu. Pengambilalihan tanah orang Marena oleh PD Sulteng untuk perkebunan Cengkih, menurut kedua tokoh ini dan sebagian besar masyarakat adat Marena, telah meninggalkan rasa sakit hati yang terus dikenang. Mereka tidak mendapat ganti rugi apa pun. Sebagian warga yang mendapat ganti rugi, hanya memperoleh Rp 2.500/ha. Seorang tokoh lembaga adat dari kalangan perempuan, Yenny, menyampaikan rasa ketidakadilan tersebut ketika masyarakat melakukan negosiasi pengembalian tanah dengan jajaran petinggi PD Sulteng, sebagai berikut “karena pengkaplingan lahan oleh PD Sulteng, suami-suami kami tidak lagi dapat bekerja karena tidak punya lahan lagi untuk diolah, karena kami tidak punya tanah lagi. Olehnya hal ini dapat dipertimbangkan oleh bapak-bapak di PD Sulteng untuk mengembalikan lahan kami” 28 Tanah PD Sulteng tersebut dulunya merupakan kawasan pertanian dan tempat penggembalaan ternak orang Marena. Sepeninggalan PD Sulteng, tanah tersebut tidak lagi terawat tapi larangan pemanfaatan tanah masih terus berlanjut. Masyarakat Adat Marena memperoleh informasi bahwa 25 ha dari tanah itu sudah dimiliki oleh dua orang pengusaha dari Palu. Sebuah informasi yang membuat mereka semakin merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah. Karena itu, mereka berupaya menggarap tanah secara diam-diam, meski sering kali berada di bawah bayang-bayang intimidasi aparat kecamatan. Sepanjang periode 1990-an sampai awal 2000, pemanfaatan tanah secara diam-diam adalah kegiatan sembunyi-sembunyi. Beberapa kali tokoh adat dipanggil pihak kecamatan untuk memastikan tanah PD Sulteng tidak diambilalih warga. Alex Sibala dan direktur PD Sulteng sendiri dihukum karena korupsi dana penghijauan. Sementara PD Sulteng menunggak pajak lebih dari 50 juta rupiah. Memang ada komitmen lisan PD Sulteng untuk mengembalikan tanah tersebut tapi menyerahkan keputusan formal ke tangan Gubernur. Menurut warga, situasi yang semrawut dan memperlihatkan bobroknya PD Sulteng seharusnya menjadi alasan untuk mengembalikan tanah tersebut secara resmi ke masyarakat adat Marena. Namun, tanah itu tak kunjung kembali. Perjuangan mereklaiming tanah tersebut sudah dilakukan dan atas inisiatif lembaga adat tanah tersebut dibagikan ke masing-masing warga. Tapi pengakuan pemerintah, yang mereka tunggu, tidak kunjung muncul. Masyarakat Adat Marena merasa bahwa pemerintah masih enggan melepaskan tanah bekas PD Sulteng secara formal karena mereka masih memiliki misi terselubung. Alasan formalnya, alas hak PD Sulteng adalah hak pengguna-usahaan yang harus dikembalikan ke Gubernur. Untuk mendpatkan hak baru, harus ada bentuk pelepasan dari hak pengguna-usahaan ke hak baru tersebut. Namun hak pengguna-usahaan sangat suram dalam hukum nasional. Lihat Box 5. Box 5: Hak Pengguna-usahaan Hak pengguna-usahaan keluar dari dapur Departemen dalam Negeri. Hasil dari fragmentasi Departemen akibat manajemen sektoral juga menghasilkan kebijakan-kebijakan sektoral. Dalam urusan tanah, tidak hanya BPN yang memiliki kewenangan mengatur pertanahan, tapi juga departemen-departemen lain, termasuk Depdagri. Penyebutan konsep hak pengguna-usahaan sulit dicari rujukan definisinya, tapi secara normatif, tertuang dalam sejumlah peraturan. Misalnya, Perda DKI No. 5 Tahun 1997 ttg Penyertaan Modal Daerah DKI dalam Pembentukan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta menyebut pengguna-usahaan tanah hasil reklamasi. Dalam skema peraturan tersebut, hak pengguna-usahaan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Hak Pengelolaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Skema selanjutnya mengikuti skema UUPA, yakni di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perseroan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) Induk . Pasca-reformasi, sebutan hak pengguna-usahaan dikeluarkan dalam beberapa peraturan Menteri dalam 27 Dokumen Advokasi LPA Awam Green. Catatan LSM LPA Awam Green dalam dialog dengan PD Sulteng (5 Juni 2001, pukul 14.00 WITA, Kantor PD Sulteng). 28 15 Negeri. Pasal 1 angka 29 Kepmendagri No. 11 Thn 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyebut pengguna-usahaan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga. Pengguna-usahaan sebagai bentuk pemanfaatan juga disebut dalam materi diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, Departemen dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (Juni 2007), modul 3. Di sana disebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik adalah penyewaan, pinjam pakai dan pengguna-usahaan. Hak pengguna-usahaan bukan merupakan hak yang berasal dari UUPA. Dalam tuntutan orang Marena, hak yang mereka inginkan adalah hak adat, sebagaimana disebutkan dalam UUPA, pasal 3: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Tuntutan pengakuan hak ulayat diajukan berdasarkan klaim bahwa orang Kulawi Moma di Marena adalah masyarakat adat. Dalam surat resmi ke Gubernur Sulawesi Tengah, warga Marena berharap bahwa tanah yang sudah mereka kelola diakui secara resmi oleh Gubernur sebagai tanah adat Marena. Kedua, kehadiran migran. Pada 2000, Indonesia menempati urutan ketiga produsen kakao terbesar dunia. Sebagian besar produksi disumbang oleh petani-petani kecil dari Sulawesi (Li 2007:110). Dalam sejarah kakao di nusantara, Sulsel sudah mengenalnya sejak lama, kurang lebih pada periode 1820-1880 (Faust et al. 2003:12). Tapi, di Sulteng kakao diperkenalkan ke masyarakat setempat baru pada tahun 1980-an oleh migran dari Bugis. Warga setempat mengakui, jika tidak diperkenalkan oleh orang Bugis mereka sama sekali tidak mengenal kakao dan keuntungan ekonomi yang dihasilkannya (Li 2007:109). Lihat Box 6: Box 6: Migran dan Kebutuhan Akan Tanah Hidup koeksisten dengan etnis lain merupakan sesuatu yang lumrah dalam sejarah suku-suku di pinggiran Taman Nasional Lore Lindu. Sejak 1950-an, mereka sudah menerima migrasi besar-besaran yang terdiri dari orang Seko dan Rampi dari Sulsel yang mencari suaka akibat pemberontakan DI/TII Kaharmuzakar. Hingga penghujung 1980an, suku-suku lain, seperti Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Flores juga masuk ke sana tapi tidak dalam jumlah yang besar. Namun, pada era 1990-an, migrasi spontan Bugis/Mandar dari Sulsel mulai meningkat. Dalam survei yang dilakukan STORMA 2000/2001, motif migrasi spontan tersebut terutama dipicu oleh ketersediaan tanah (45%) dan kesempatan kerja (39%) (Faust et al. 2003:11). Mereka mendapatkan tanah lewat jual beli dengan masyarakat setempat atau dipandu oleh para “bos”, jaringan sosial sebagai pedagang atau petani Bugis. Para calon migran bahkan menyewa bis dari Sulsel untuk mencari tanah yang cocok di Sulteng. Pemandu yang sudah beberapa dekade mendiami dataran tinggi Sulteng memfasilitasi kedatangan mereka dan menghubungkan dengan broker penjualan tanah (Li 2007:109-11). Jaringan ini semakin intensif ketika permintan kakao meningkat. Di Watumaeta, wilayah Napu, Sekertaris Desa yang baru menyadari jumlah kaum migran Bugis begitu besar pada tahun 2001 yakni 63% dari jumlah penduduk. Perkembangan serupa terjadi di daerah lain, seperti Sigi Biromaru, Palolo, Kulawi dan Lore Utara (Li 2007:111, 311). Statisktik yang sama diperlihatkan di Tuva. Komposisi penduduk pada tahun 2004 adalah orang Sinduru (5%), Mandar (25%), Bugis (20%), Toraja (10%), Seko (10%), Kaili (20%), lain‐lain (10%). (Dokumen Advokasi LPA Awam Green 2001). Kehadiran migran para pemburu kawasan baru (tanah) menghadirkan sejumlah kondisi. Pertama peningkatan jumlah penduduk yang bergantung pada tanah, apalagi dengan skala yang luas untuk perkebunan kakao, juga meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan atas tanah. Pembukaan kawasan taman nasional dan wilayahwilayah baru semakin meluas. Di Tuva, sebagian besar warga dusun dua, yang umumnya migran memiliki kebun di kawasan Taman Nasional. Kedua, kehadiran migran di penghujung 1990-an hingga 2000-an diikuti dengan rentetan 16 persoalan komunikasi dan relasi dengan masyarakat setempat. Migran Seko, Rampi dan migran lain dalam periode sebelumnya, meminta izin secara resmi kepada kepala adat untuk diperbolehkan tinggal di tempat itu. Kepala adat selanjutnya membagikan mereka tanah. Sementara, migran Bugis/Mandar yang menghuni tepian kawasan atau di dalam kawasan Taman Nasional, dipandu oleh para broker tanah dan jaringan etnisnya sendiri, sehingga sering kali di luar jangkauan lembaga adat dan administrasi desa. Banyak di antaranya tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga menyulitkan komunikasi. Secara perlahan komunitas-komunitas pendatang ini menjadi eksklusif. Letupan konflik kerap terjadi, sering kali hanya dipicu oleh sindiran yang remeh-temeh. 29 Perkembangan ekonomi di awal tahun 2000 tersebut pada giliran berikutnya juga memicu peningkatan transaksi tanah dan meningkatkan jumlah penduduk. Mahori dan Arifin mengakui bahwa pembukaan kawasan taman nasional di wilayah Tuva dan sekitarnya mulai terjadi secara besar-besaran pasca-tahun 2000-an. Umumnya daerah baru tersebut ditanami kakao. Pionirnya adalah migran Sulsel. Pada pendatang ini menjadi kelompok ekonomi baru yang mendapatkan tanah dalam jumlah yang luas dari warga setempat maupun pembukaan taman nasional, sementara warga setempat semakin kehilangan tanah. Mereka membangun etos kerja sebagai perantau yang kompetitif membuka dan mengerjakan lahan (Sitorus 2002:9-11). Dalam pandangan tokoh-tokoh adat Marena dan Tuva, kaum pendatang ini harusnya menghormati adat istiadat setempat dengan mengakui hukum adat setempat. Dalam mengakses tanah, seharusnya mereka minta restu lembaga-lembaga adat sebagaimana sudah terjadi pada generasi pendatang sebelumnya. Seperti kata Mahori, “Tidak ada pembukaan tanah main sembarang begitu, dulu harus izin lembaga adat dan dibagi oleh lembaga adat. Orang tua saya selaku kepala adat dulu membagikan tanah ke pendatang dan orang Sinduru.” Mahori, Arifin, Maida dan beberapa tokoh adat Sinduru menegaskan perlunya mengembalikan situasi di Tuva ke dalam kontrol adat, bukan ke tangan kepala desa. Pemerintah Desa harus mengakui masyarakat adat dan wilayah adat. Penegasan ini selanjutnya dihubungkan dengan kearifan ekologis yang dimiliki masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Di bawah kontrol adat, hutan adat yang juga merupakan hutan konservasi dan hutan lindung, masih terjaga. Ketika kontrol adat diambilalih pemerintah (desa), justru kawasan konservasi dijarah. Apalagi, kepala desa saat ini dipegang oleh orang yang berasal dari etnis mayoritas yang menjadi pionir pembukaan kawasan taman nasional. Orang Sinduru yang jumlahnya minor sangat rentan dituduh sebagai pelaku perambahan taman nasional. Situasi ketidakadilan ini hanya bisa diatasi jika kewenangan adat atas wilayah Tuva dikembalikan dan untuk itu Peraturan Daerah yang menempatkan adat di bawah kontrol desa harus dicabut. Menurut Arifin, Peraturan Daerah yang seharusnya ada adalah Perda yang mengakui hak-hak masyarakat adat sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan merujuk pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 UUD 1945, Arifin menyampaikan bahwa hak masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diingkari negara. Pengingkaran merupakan pelanggaran sistematis oleh negara atas hak-hak konstitusional masyarakat adat. Analisis Hukum 29 Arifin, wawancara di Tuva, 27-2-2009. 17 Masalah akses tanah di kawasan hutan sebagiannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di skala nasional. Rujukan utamanya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lihat Box 7. Box 7: 1) 2) 3) Pasal 67 Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. a. Syarat-Syarat Undang-undang ini memberi ruang dalam batasan tertentu terhadap masyarakat hukum adat, bukan masyarakat adat. Namun, tidak ada kejelasan mengenai relasi antara konsep masyarakat hukum adat dengan konsep indigenous peoples. Pasal ini hanya menyebut dua hal penting dalam hubungannya dengan syarat terhadap masyarakat hukum adat yakni: pertama, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan kedua, jika keberadaannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam bagian lain, pasal 4 ayat 3 undang-undang ini, tercantum syarat lain yakni sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Syarat-syarat ini juga berkembang biak dalam peraturan-peratuan yang lain seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hingga UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam temuan Rikardo Simarmata, syarat-syarat ini sebagiannya merupakan kelanjutan dari ketentuan yang berlaku pada era kolonial Belanda. Namun, pada era pemerintah kolonial Belanda syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat dicantumkan untuk mengakui hukum adat dan pemerintahan desa. Tetapi, pasca-kemerdekaan, syarat-syarat ini berkembang biak ke objek-objek lainnya, antara lain hak ulayat, hukum adat, mengatur adat istiadat, kebiasaankebiasaan masyarakat dan lembaga adat (Simarmata 2006: 309-14). Di Kabupaten Donggala, skema pengakuan hukum masyarakat adat di tingkat nasional juga diterapkan dalam Perda Kabupaten Donggala No. 13 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Dalam perda ini, berbagai promosi dan dukungan terhadap masyarakat adat, selain menekankan kekhususan masyarakat adat, juga mendorong terbentuknya struktur-struktur baru dalam lembaga adat. Perda tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melalui unit desa memfasilitasi maupun membentuk lembaga-lembaga adat untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong 18 mensejahterakan warga masyarakat setempat. 30 Struktur baru dalam Perda tersebut melahirkan beberapa lembaga adat bentukan baru seperti pitu nggota yang mengklaim diri sebagai lembaga adat yang mendapat mandat sebagai pemimpin lembaga-lembaga adat lainnya di tingkat kabupaten. Perda ini juga menyebutkan bahwa bupati merupakan pembina lembaga adat, semacam “raja” adat yang posisinya berada di atas semua struktur adat di tingkat kampung, desa dan kecamatan. b. Kelembagaan Dalam semua peraturan perundang-undangan yang mengakui masyarakat adat saat ini, tidak begitu jelas lembaga mana yang TUPOKSI-nya (tugas pokok dan fungsi) mengatur dan mengurus masyarakat hukum adat sebagai entitas yang utuh, tidak terpecah-pecah berdasarkan sektor. Ketiadaan lembaga semacam itu membuat pengaturan tentang masyarakat hukum adat menjadi kesulitan dalam program. Dalam temuan Rikardo di sejumlah daerah, pertanyaanpertanyaan teknis seperti, lembaga mana yang mengajukan anggaran untuk melaksanakan identifikasi hak ulayat justru menjadi persoalan yang hampir sama sulitnya dengan pemahaman tentang masyarakat adat itu sendiri (Simarmata 2006:339-45). Situasi ini ditegaskan oleh Yanis, Kepala Bagian Umum dan Informasi BPN Provinsi Sulteng yang melihat tidak ada inisiatif pemerintah daerah untuk mengakui tanah ulayat sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah harusnya segera membentuk tim untuk melakukan penelitian mengenai tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Yanis, kegiatan ini belum dimulai di Sulawesi Tengah, sehingga status klaim tanah-tanah adat, secara hukum belum jelas. Masalah pendanaan juga diuraikan Yannis. Tidak ada alokasi khusus dalam APBD untuk mengidentifikasi maupun meregistrasi tanah-tanah ulayat, sehingga upaya-upaya melakukan identifikasi tanah, sebagaimana dikerjakan BPN, dilakukan berbasis TUPOKSI masing-masing sektor, tidak dikerjakan secara bersama-sama yang melibatkan banyak sektor. Akibatnya, sering kali terjadi tumpang tindih klaim tanah atau wilayah, terutama antara masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan. 31 Dalam kaitannya dengan pengaturan peruntukan dan distrisusi tanah, BPN merupakan lembaga yang memiliki peran sentral. Menurut Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pertanahan Nasional, memiliki sejumlah fungsi. Dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006, fungsi BPN, antara lain: a. b. c. d. e. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus; penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan; pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; 30 Dalam studi Simarmata, inisiatif Perda ini tidak semata-mata didorong oleh reformasi tapi sudah terbentuk sejak lama di bawah panduan yang telah disediakan oleh Depdagri di bawah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak tahun 1984 melalui Permendagri No 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan. Lihat Simarmata (2006:79-80). 31 Yannis, wawancara 5-3-2009, di Palu. 19 Fungsi ini dalam kaitannya dengan akses masyarakat adat terhadap tanah sudah diatur dalam peraturan sebelumnya, Peraturan Mentri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menyebutkan beberapa langkah institusional dalam pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (pasal 5), yakni: 1. 2. Penelitian dan penentuan masih adanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Namun fungsi BPN, tidak bisa bekerja dalam kawasan konservasi dan kehutanan. Aturan dan otoritas pada areal konservasi merupakan bagian dari regim hukum konservasi dan kehutanan, dalam hal ini Departemen Kehutanan. Otoritas tersebut berasal dari politik hukum sumber daya alam sejak awal Orde Baru. Dalam sejarah Orde baru, dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan segera dikenal konsep kawasan hutan negara yang merupakan interpretasi lebih lanjut dari pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Istilah “dikuasai oleh negara” dalam kawasan hutan dikenal dengan istilah “hutan negara”. Istilah ini kemudian melebar dalam berbagai strategi dan pelaksanaan fungsi departemen kehutanan. Sebagaimana dipaparkan McCarthy: Untuk memperkuat penguasaan negara atas wilayah hutan luas yang ditemukan di wilayah ini, pemerintah Orde Baru memulai serangkaian pelatihan pemetaan hutan. Pelatihan pemetaan ini bertujuan untuk mengatasi masalah perencanaan antara pelbagai sektor Negara untuk membantu pengembangan industri kehutanan dengan memfasilitasi alokasi hak pengusahaan atas tanah hutan. Puncak dari proses ini terjadi pada 1980, ketika Menteri Pertanian (kemudian bertanggung jawab untuk kehutanan) meminta masing-masing gubernur provinsi (di daerah luar Jawa) mempersiapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK. Menurut klasifikasi TGHK terdapat 143.800.000 ha permukaan tanah di Indonesia (sekitar 75% dari wilayah negara) sebagai “tanah hutan” – wilayah tanah yang kemudian berada di bawah jurisdiksi Departemen Kehutanan ((Mc Carthy 1999:3-4) Berdasarkan konsep TGHK maka kawasan hutan taman nasional, hutan lindung maupun hutan produksi terbatas di Tuva dan Marena dikategorikan sebagai hutan negara. Di situ terjadi tumpang tindih klaim antara klaim wilayah adat oleh berbagai komunitas adat termasuk Tuva dan Marena. c. Larangan di Area konservasi Sebagai kelanjutan dari besarnya porsi kewenangan Departemen Kehutanan di kawasan konservasi, kontrol terhadap kawasan tersebut diambil sepenuhnya oleh birokrat dari Departemen Kehutanan. Di kawasan yang diklaim sebagai wilayah adat Tuva maupun Marena, hukum konservasi juga berlaku secara ketat. Menurut Yakobus, pejabat PPNS di Balai Besar 20 Taman Nasional Lore Lindu, Balai Taman mengedepankan hukum negara terutama UndangUndang Konservasi No. 5 Tahun 1990, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 untuk melarang aktivitas apa pun dalam kawasan hutan konservasi. Dalam salah satu pasal UU Kehutanan disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang: (a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (b) merambah kawasan hutan; (c) membawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Rumusan ini sering kali menjadi pasal tuntutan atas warga Sinduru yang diduga melakukan pelanggaran (lihat Box 8). Box 8: Penerapan Kebijakan Taman Nasional Sahrun, seorang warga Sinduru, pernah dipanggil Balai Taman Nasional karena tuduhan merambah kawasan Taman Nasional berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 78 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999. Sahrun merasa tuduhan pelanggaran atas dirinya dan keempat orang adiknya tidak adil. Menurut dia, daerah yang mereka buka adalah bekas kebun nenek moyang mereka ketika kampung Tuva masih berada di lereng bukit. Setelah Tuva bergeser ke dataran rendah seperti saat ini, kawasan yang ditinggalkan tersebut dikategorikan sebagai kawasan Taman Nasional. Sahrun tahu ada larangan membuka kawasan Taman Nasional, namun banyak orang lain yang sudah membuka kawasan tersebut, meskipun mereka bukan orang Sinduru. Kata Sahrun, “Daripada daerah itu habis dirambah orang lain, lebih baik kita yang punya hak ini cepat-cepat paras (membuka kawasan) juga”. 32 Dokumen resmi Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu No. LK/02/III/2008 tanggal 8 April 2008 menyebutkan saksi pelapor dalam kasus Sahrun adalah seorang migran (Abdul Manaf, Kepala Dusun I, Desa Tuva) yang menurut orang Sinduru tidak paham dengan sejarah wilayah adat orang Sinduru. Di kepala Sahrun, kehadiran Taman Nasional memang menjadi salah satu masalah utama bagi orang Sinduru, terutama dalam akses atas tanah. Berharap pada Lembaga Pemerintah Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat Kulawi Moma di Marena dan Sinduru di Tuva sering kali menghadapkan mereka pada beberapa forum yang menawarkan diri seperti BPN maupun yang hadir karena forum tersebut langsung bersinggungan dengan tanah yang dikuasai atau diklaim sebagai wilayah adat, dalam hal ini Balai Taman Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Beberapa kali, pejabat BPN melakukan kunjungan lapangan ke Marena. Namun kehadiran mereka kurang mendapat respons, dalam arti penyampaian klaim, oleh warga. Beberapa tokoh adat di Marena seperti Rince dan Fredy, merasa tidak begitu penting berhubungan dengan BPN yang tidak banyak berurusan dengan kawasan hutan. Selain itu, anggota masyarakat tidak tahu benar peran dan kerja lembaga tersebut. Peran BPN yang pernah mereka temukan adalah mereka pernah mendapat tawaran dari Dinas Pertanahan Donggala untuk mensertifikatkan tanah melalui program Prona. Prona adalah program dalam sistem ajudikasi dengan biaya sangat murah agar masyarakat bisa mengakses dengan lebih mudah. Namun pengalaman Rince dan warga di Marena, program sertifikat dengan sistem ajudikasi (Prona) pernah berjalan tetapi dengan biaya yang tidak terjangkau oleh sebagian besar warga Marena kecuali segelintir pengusaha. Untuk pendaftaran hak atas bangunan (rumah) dikenakan biaya administrasi Rp 800.000. Untuk tanah pertanian, jumlahnya lebih dari 1 juta. Dalam hal ini, BPN lewat Prona, menjadi forum yang hadir tapi tidak diakses warga. 32 Sahrun, wawancara 27-2-2009, di Tuva. 21 Masyarakat juga pernah menghabiskan banyak biaya ketika kasus mereka dibawa ke lembaga-lembaga pemerintah. Pengalaman itu, menurut Arifin, membuat mereka menahan diri, sedapat mungkin tidak membawa kasus ke lembaga pemerintah atau aparat hukum. Lihat Box 9. Box 9: Berkorban untuk Sejengkal Tanah Dalam kasus pembukaan kawasan hutan adat Tuva oleh CV Satria Abadi dan Koperasi Unit Desa Singganiyang, masyarakat melakukan lobi dan negosiasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Mereka menjual ayam, anyaman rotan bahkan kambing agar bisa melakukan lobi ke Palu. Mahori misalnya melepaskan kambingnya di Kecamatan Gumbasa agar memiliki bekal dana ke Palu. Meskipun penguasaan KUD dan CV Satria Abadi yang lebih dari 20 hektar itu dilarang oleh UU No. 56 Prp 1960, fungsi BPN tidak bekerja dengan efektif. Menurut Yannis, belum terwujudnya kelembagaan mengenai masalah tanah ulayat di tingkat daerah merupakan sebab utama mengapa upaya pendaftaran tanah-tanah ulayat belum berjalan di Sulawesi Tengah. Namun, menurut Rince, di Marena peran sertifikasi justru terjadi untuk wilayah sengketa antara orang Marena dengan PD Sulteng. Ada isu suap di belakang peran tersebut karena meskipun sengketa tersebut telah sampai ke gubernur, beberapa pihak dari Palu serta-merta mengklaim telah memiliki sertifikat milik atas tanah sengketa tersebut. Balai Taman Nasional Balai Taman Nasional merupakan forum yang selalu mengalami perjumpaan dengan masyarakat adat Marena dan Sinduru. Kehadirannya yang mengklaim wilayah yang juga diklaim sebagai wilayah adat mengakibatkan tegangan tapi juga negosiasi atas akses terhadap tanah. Di Marena, Balai Taman Nasional menandatangani kesepakatan konservasi bersama masyarakat dengan memberi pengakuan atas wilayah adat yang berada dalam kawasan taman nasional dan memberi mandat bagi lembaga adat untuk mengkontrol kawasan tersebut. Masyarakat adat Marena pun memberlakukan hukum adat di wilayah itu dan menjatuhkan sanksi-sanksi adat atas para pelaku yang masuk tanpa izin lembaga adat di wilayah itu. Namun, jika penyelesaian masalah tidak tuntas secara adat, misalnya, pernah terjadi pelaku membangkang terhadap keputusan adat, maka lembaga adat membawa kasus tersebut ke hukum negara, dalam hal ini ke Balai Taman Nasional dan Kepolisian. Pola ini tidak hanya menunjukan forum yang majemuk tapi juga lapisan forum. Di Marena, forum adat masih membatasi diri pada kasus-kasus yang bisa ditangani secara adat. Sebagaimana dikatakan oleh Rince dan Fredy, forum adat akan mengadili kasus agar menimbulkan damai atau ketenangan dalam wilayah Marena. Jika terjadi keonaran maka forum itu diserahkan ke pihak kepolisian. 33 Bermuara pada Lembaga Adat Dalam hukum adat Sinduru dan Kulawi Moma, lembaga adat memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus adat maupun membentuk hukum adat. Lembaga adat di sini adalah dalam pengertian forum bukan perorangan yang secara tidak sengaja ada untuk menangani ketidakadilan dan keluhan warga, penggunaan kata aturan atau prinsip mengindikasikan bahwa akses kepada keadilan memerlukan aturan atau prinsip yang memandu prosedur menuju hasil 33 Fredy dan Rince, wawancara 3-3-2009, di Marena. 22 (Bedner dan Vel 2009:12). Meski demikian, efektitivitas lembaga adat sebagai forum juga ditentukan oleh peranan tokoh adat, baik dalam kedudukan menjadi perantara pengaduan masyarakat adat ke forum yang lain, seperti pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, juga dalam perilaku individual yang memberikan contoh dan panutan bagi warga adat. Untuk kedudukan yang terakhir ini, Nixen memberi gambaran spesifik mengenai kriteria orang-orang yang mengisi lembaga adat di Marena, antara lain keteladanan, moralitas, kemampuan merumuskan hukum adat, diterima warga. Perilaku individual menentukan peranan sebagai anggota lembaga adat dan demikian sebaliknya. Keduanya saling mendukung dalam penyelesaian sengketa adat. Saya menyebut wewenang penyelesaian sengketa dan pembentukan hukum adat sebagai forum pengaduan. Sementara peran adat dalam mengartikulasikan pengaduan masyarakat adat saya kategorikan sebagai forum pengadu. Dalam dua kategori ini, peta dinamika lembaga adat tampak berbeda antara Kulawi Moma di Marena dan Sinduru di Tuva. Dalam konteks forum pengadu, mulai pertengahan 1990-an, sejumlah tokoh adat dari Marena berusaha mengkomunikasikan situasi warga tanpa tanah ke Camat Kulawi waktu itu, Livingstone Sango. Mereka mengajukan permintaan agar tanah yang tidak terawat oleh PD Sulteng dikembalikan ke warga. Namun camat bersikukuh bahwa tanah itu adalah milik PD Sulteng. Pasca-reformasi 1998, artikulasi pengaduan orang Marena semakin diperkuat oleh tokohtokoh lembaga adat. Nixen, Rince, Yohanes, dan Yenny adalah sejumlah tokoh adat yang aktif memperjuangkan pengembalian tanah adat eks-perkebunan PD Sulteng. Sebagai artikulator, ada beberapa tingkat sikap yang mereka temui. Pertama, sikap camat masih ombang-ambing menjawab tuntutan warga. Ketika para tokoh meminta camat untuk menandatangani pernyataan setuju atas reklaiming, dia menghindar dengan alasan dia aparat negara. Kedua, Sikap aparat Desa lebih mendukung gerakan reklaiming. Kepala Desa Bolapapu yang membawahi Marena, selalu menandatangani surat-surat tuntutan warga yang terartikulasi lewat lembaga-lembaga adat. Sementara Kepala Dusun Marena, Rince, lebih menempatkan diri sebagai perwakilan masyarakat dengan mendukung dan menyuarakan segala bentuk usulan pengembalian tanah ke berbagai forum pemerintah. Ketiga, lembaga pemerintah pada tingkat kabupaten di Donggala kurang sering ditemui warga karena jarak yang jauh. Ongkos transport bisa puluhan ribu. Di sana belum tentu mereka bisa menemui pejabat terkait. Mereka sendiri tidak begitu mengenal lembaga pemerintah mana yang menjadi tujuan komplain. Sejumlah tokoh adat pun hanya mengenal BPN sebagai lembaga yang mengurus tanah, Dinas Kehutanan mengurus masalah kehutanan dan DPR tempat mengadukan segala tetek bengek persoalan. Fungsi detail dan peranan masing-masing lembaga tersebut masih kabur dan gelap. Sehingga, bersama sejumlah NGO, komplain dan pengaduan kerap dilakukan melalui surat yang dibawa oleh aktivis NGO dari Palu ke lembaga-lembaga yang bersangkutan. Aktivis NGO inilah yang mengemas kembali surat-surat tersebut dalam bahasa yang layak untuk disampaikan ke berbagai instansi pemerintah tersebut. Sebagai forum pengaduan, bagi masyarakat Marena, Lembaga Adat Marena mewujudkan kebutuhan mereka atas tanah. Para pendatang juga merasa lembaga adat memfasilitasi mereka dan tidak pernah mengintimidasi pendatang. Lihat Box 10. Box 10: Lembaga adat Marena di Mata Migran Ibu Ismawati, seorang etnis Toraja, sudah 10 tahun tinggal di Marena. Sejak lama dia dan keluarganya tidak memiliki tanah. Kehidupan sangat susah, sementara mereka punya tiga orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan 23 hidup sehari-hari, Ismawati dan suaminya meminjam tanah tetangga untuk ditanami jagung dan sayur-sayuran. Dari tanah pinjaman tersebut mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Pada tahun 2000, keluarga Ismawati mulai mengerjakan bidang tanah yang ditelantarkan PD Sulteng. Lembaga Adat Marena mendukung upaya sporadik warganya. Di mata Ismawati, lembaga adat melindungi mereka, tidak berlaku kasar dan semena-mena. Dalam penyelesaian sengketa adat, mereka juga dimintai pertimbangan dan pendapat mengenasi kasus yang diadili. Sehingga, bagi Ismawati, orang Marena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. 34 Ismawati sendiri bisa berbahasa Kulawi sehingga mudah melakukan komunikasi dengan orang Kulawi Moma, sebagai penduduk asli di Marena. Kehadiran migran tidak menjadi masalah yang serius di Marena. Mayoritas etnisnya adalah Kulawi Moma, sehingga hukum adat yang dipakai adalah hukum adat Kulawi Moma. Namun, masalah migran muncul pasca-pembukaan taman nasional oleh etnis Mandar/Bugis untuk perkebunan kakao. Masalah tersebut sulit terselesaikan dalam lembaga adat karena menurut tokoh-tokoh adat, selain karakter pelaku yang keras juga tidak ada inisiatif dari pihak balai taman nasional untuk menegakkan hukum dalam kasus tersebut. Padahal sudah ada kesepakatan tertulis antara Marena dan Balai Taman Nasional. Lihat Box 11. Box 11: Penegakan Hukum Adat Beberapa orang migran Mandar/Bugis yang dipelopori Umar Paewah membuka kebun di kawasan taman nasional diajukan dalam sidang adat. Namun, adat tingkat Dusun merasa perlu mengajukan kasus tersebut ke lembaga adat di tingkat desa karena pelaku terlanjur resisten sembari mengeluarkan kata-kata penghinaan. Untuk meredakan amarah warga di tingkat dusun, maka lembaga adat desa menyelesaikan kasus tersebut. Desa menjatuhkan hukuman Rongu Rompulu Rongkau yang disetarakan dengan uang Rp 1.250.000 kepada umar Paewah. Namun sanksi yang dijatuhkan tidak ditaati pelaku. Para tokoh adat menyerahkan implementasinya kepada pihak Balai Taman Nasional agar pelaku segera diperiksa karena membuka kebun dalam kawasan taman nasional. Apa yang terjadi justru sebaliknya, Kepala Satpolhut yang merupakan orang Bugis, mendatangi rumah pelaku dan berbicara dengan menggunakan bahasa Bugis sebagai media komunikasi. Hingga saat ini, pelaku tidak sekalipun diperiksa oleh Balai Taman Nasional. Bagi ibu Yenny, perlakuan tersebut adalah diskriminasi berbasis etnis, tapi juga sekaligus alasan untuk semakin memperkuat adat. Struktur adat Marena relatif baru. Didukung oleh kehadiran Perda dan pernyataan lisan bupati yang mendukung pembentukan lembaga-lembaga adat, Marena juga mereorganisasi lembaga adatnya. Beberapa etnis migran seperti Jawa, Toraja dan Kaili diundang sebagai representasi etnik dalam lembaga adat. Selain itu, Rince selaku Kepala Dusun Marena lebih kerap menggunakan argumen adat daripada peraturan negara. Posisinya sebagai kepala dusun turut mendukung lancarnya komunikasi antara Marena dengan Kepala Desa di Bolapapu. Peran perempuan juga diakui dalam lembaga adat Marena. Seorang tokohnya, Yenny Buha, mewakili struktur perempuan adat juga aktif dalam sidang-sidang adat. Dalam negosiasi dan lobi untuk mendapatkan kembali tanah dari PD Sulteng, Yenny Buha menjadi perempuan yang paling aktif di semua tingkat gerakan, baik dalam komunitas Marena maupun tindakan keluar. Menurut Yenny, kalau dia tidak berjuang, siapa lagi yang akan memperjuangkan tanah untuk kehidupan anak-anak mereka di masa depan. 35 Posisi Yenny juga didukung oleh tokohtokoh lembaga adat lain, seperti tokoh berpengaruh dari kalangan pemuda Nixen, kepala dusun Rince, dan seorang pemangku adat, Gapar. Dukungan para tokoh tersebut membuat Yenny selalu diberi kesempatan berbicara dalam forum-forum adat. 34 35 Ismawati, wawancara 4-3-2009, di Marena. Yenny Buha, wawancara 17-2-2009, di Palu. 24 Seorang tokoh lain, Fredy, adalah seorang pendeta. Sebagai tokoh agama mayoritas di Marena, pandangannya yang luas karena latar belakang pendidikan yang memadai dan jaringan dengan berbagai LSM lokal maupun nasional membuat informasi-informasi yang disampaikan sering kali menjadi rujukan tokoh adat lainnya. Sebelum pindah ke Marena, 2001, Fredy adalah pendeta di Ngata Toro, sebuah wilayah yang menjadi rujukan daerah lain karena adanya pengakuan hak masyarakat adat, tidak hanya dari pemerintah Indonesia tapi juga dari badan dunia UNESCO. 36 Latar belakang itu juga mendorong Fredy untuk memperjuangkan hak masyarakat adat Marena. Dukungan Fredy dalam berbagai bentuk, memberikan kontribusi penting dalam menjadikan Marena sebagai kampung kedua, setelah Toro, yang wilayah adatnya dalam taman nasional diakui secara resmi oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu. Dalam menjalankan peran sebagai forum pengaduan, upaya penyelesaian sengketa maupun pembuatan keputusan adat dalam sidang-sidang adat senantiasa melibatkan warga marena, termasuk etnis lain. Dalam upaya reklaiming tanah PD Sulteng, lembaga adat melakukan upaya kolektif melibatkan semua etnis. Selain itu, berbagai aktivitas, seperti peresmian rumah ibadah, pembukaan sekolah di bekas reklaiming dan penyelesaian sengketa, direlasikan dengan adat atau merujuk pada adat. Dalam pelaksanaannya, mereka mengundang berbagai institusi negara, seperti Koramil, Kepolisian, Kecamatan, Desa bahkan Bupati dan DPRD. Sebagian besar institusi negara tersebut mendukung acara-acara tersebut dengan berbagai versi. Bupati, misalnya, mendukung pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan dikembalikan ke masyarakat adat. DPRD mengusulkan agar daerah sebaiknya memiliki wewenang atas taman nasional, sehingga masyarakat adat juga bisa dilibatkan. 37 Berbagai dukungan tersebut akhirnya menempatkan lembaga adat versi baru sebagai intitusi yang tampil di tingkat bawah yang menjadi harapan warga dalam penyelesaian banyak sengketa, termasuk pengatur distribusi sumber daya, terutama tanah. Dalam distribusi tanah, peran lembaga adat Marena pun sangat signifikan terutama untuk menjamin semua warga mendapatkan haknya. Lihat Box 12. Box 12: Distribusi Tanah oleh Lembaga Adat Pasca-peresmian reklaiming tanah PD Sulteng oleh orang Marena, Lembaga Adat mengeluarkan aturan mengenai distribusi dan larangan-larangan dalam pemanfaatan tanah. Dalam konteks distribusi, 15X15 m² dialokasikan untuk perumahan, 0,5 ha-1 ha untuk tanah pertanian. Sebagian penduduk yang tak bertanah mendapat jatah 1 ha. Sementara penduduk yang sudah memiliki tanah, umumnya mendapatkan tanah 0,5 ha. Sisa pembagian tersebut dialokasikan untuk sekolah, bangunan ibadah dan rumah pertemuan. Di mata migran, seperti Ismawati, peran lembaga adat dalam distribusi tanah diterima sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan bagi warga, termasuk pendatang. Peran tersebut, menurut Ismawati, penting untuk dipertahankan dan diperkuat. Dinamika Forum Adat: Antara Asli dan Bentukan dari Luar 36 Ngata Toro mendapat penghargaan Equator Prize dari UNESCO tahun 2004 karena dianggap melindungi biosphere di kawasan taman nasional lore lindu. 37 Fredy, wawancara 3-3-2009, di Marena. 25 Setidaknya ada dua lembaga adat yang dipicu oleh kehadiran pihak lain non-adat. Pertama adalah lembaga adat yang terbentuk karena interpretasi atas PERDA. Kedua, lembaga adat yang dibentuk karena dipicu oleh implementasi proyek NGO. a. Lembaga Adat yang Dibentuk karena Dipicu PERDA Melalui Perda, Pemerintah Daerah membentuk sebuah wadah kelembagaan adat yang disebut Pitu Nggota. Lembaga ini diberi amanat sebagai representasi adat se-Kabupaten Donggala. Dalam kasus antara Marena dan Balai Taman Nasional, lembaga ini berjuang mendapat tempat sebagai forum pengadu dan pengaduan orang Marena. Namun orang Marena tidak mengenal forum ini karena dia hadir oleh penunjukan Bupati bukan melalui proses pemilihan sebagaimana dipakai dalam pemilihan ketua dan dewan adat di Marena. Forum ini pun dianggap sebagai boneka pemerintah daerah untuk mengkontrol masyarakat adat. Lembaga bentukan baru juga memicu pembentukan sejumlah lembaga adat di tingkat desa, termasuk Desa Bolapapu, di mana wilayah Marena ada. Secara prosedural lembagalembaga adat bentukan ini memang mengikuti pola yang berlaku di masing-masing wilayah. Namun secara struktural mengikuti langgam administrasi pemerintah. Sehingga prosedur penyelesaian sengketa juga akan mengikuti struktur administrasi. Dalam hal ini, lembaga adat di tingkat dusun bisa melimpahkan kasus ke desa, dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke bupati, selaku pembina adat. Hierarki adat ini merupakan variasi baru yang secara kuat melibatkan kekuasaan politik daerah. 38 NGO seperti LPA Awam Green mengkritik Perda ini sebagai manifestasi dari feodalisme dan merusak tatanan masyarakat adat. Namun menurut Fredy, pengaturan tersebut merupakan bentuk dukungan dan perlindungan atas lembaga dan masyarakat adat. Apalagi bupati sendiri menjadi pembina yang memerintahkan pembentukan sejumlah lembaga adat, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Pada tingkat tertentu, sebagian wewenang adat untuk memastikan hukumnya bekerja efektif ikut diambil ke tingkat lebih tinggi, desa, kecamatan dan kabupaten. 39 Dalam kasus hukuman terhadap seorang pendatang di Marena, karena membuka kebun di wilayah adat yang beririsan dengan taman nasional, tersangka membangkang dan menolak hukuman adat di tingkat dusun. Untuk menghindari konflik lebih besar, kepala dusun dan para tokoh adat Marena membawa kasus ini ke tingkat adat desa. Di sana pelaku diadili dan dijatuhi hukuman adat. Namun, sekali lagi pelaku membangkang. Pada akhirnya, kasus ini diserahkan ke Polisi Hutan Taman Nasional. Namun hingga sekarang sanksi tersebut belum diterapkan. Menurut tokoh adat Marena, adat di tingkat desa kurang tegas terhadap pelaku. Jika kasus itu diselesaikan di Marena tanpa ada ketegangan, implementasi sanksi akan lebih tegas. Di sisi lain, kehadiran Perda memicu konflik politik serius antara adat dengan desa. Kasus ini terjadi di Tuva. Meskipun menggunakan konsep masyarakat adat dan didukung oleh sejumlah NGO, legitimasi dan peran sentral yang sejak lama dimainkan Lembaga Adat Sinduru justru goyah. Sebagai forum pengaduan, lembaga adat Tuva retak parah oleh konflik antar-elite lembaga adat. Perbedaan interpretasi penggunaan baruga, tempat pertemuan adat, yang baru dibangun, antara tokoh-tokoh adat memicu pertikaian. Mahori menghendaki agar semua prosesi adat dipenuhi sebelum baruga tersebut digunakan. Namun tokoh-tokoh lain menganggap aturan 38 Di beberapa tempat, struktur serupa juga dikerjakan di era Orde Baru, seperti Dewan Adat tingkat Kecamatan dan Kabupaten di Kalimantan Barat; lihat Andasputra dan Vincentius Julipin (1997:1-2). 39 Fredy, wawancara 3-3-2009, di Marena. 26 tersebut kuno. Tokoh-tokoh lain didukung oleh kepala desa yang kemudian membubarkan lembaga adat yang dipimpin Mahori dan menunjuk pengurus yang baru. Menurut Kepala Desa (Kades), pembubaran lembaga adat dilakukan berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Perda No. 13 Tahun 2001. Di sana dikatakan bahwa Kades diberi kewenangan menetapkan susunan organisasi lembaga adat (pasal 8). Kewenangan itu diinterpretasikan sebagai kewenangan untuk membubarkan lembaga adat yang lama dan membentuk yang baru. Meskipun pasal tersebut mengharuskan adanya persetujuan BPD, Kades kemudian membentuk lembaga adat baru dengan menunjuk tetua adat lain dari etnis Sinduru yang mendukung posisi Kades dan berlawanan dengan Mahori. Kesemrawutan baru pun muncul karena orang yang mengisi lembaga adat hasil penunjukan Kades tidak paham benar dengan hukum adat sehingga beberapa putusan mereka dalam peradilan adat keliru. Beberapa orang yang mengisi lembaga itu kemudian mundur karena malu. Lihat Box 13. Box 13: Lembaga Adat Bentukan Kepala Desa Pasca-pembubaran lembaga adat yang diketuai oleh Mahori, kepala desa segera membentuk lembaga adat baru. Beberapa anggotanya ditunjuk dari orang-orang bekas anggota lembaga adat sebelumnya. Sebagian lainnya ditunjuk dari orang-orang baru. Menurut Arifin, dalam satu kasus perzinahan yang diselesaikan oleh lembaga adat, keputusan lembaga adat ternyata keliru, tidak sesuai dengan tradisi Sinduru yang telah berlaku sebelumnya. Keputusan keliru ini menjatuhkan pamor lembaga adat, sehingga beberapa orang di antaranya, termasuk Arifin, mengundurkan diri. Arifin adalah migran dari Batak. Nama lengkapnya Arifin Panjaitan. Dia sudah berada di Tuva sejak 1970-an dan beristrikan orang Sinduru. Kedekatannya dan penghargaannya terhadap adat Sinduru membuat dia diterima dengan baik oleh orang Sinduru. Dia pun mendapat tempat dalam struktur adat Sinduru. Dalam kasus yang membuat malu tersebut Arifin yang paham adat istiadat Sinduru merasa malu karena seharusnya orang yang menduduki lembaga adat adalah orang-orang yang paham hukum adat. Tidak pernah ada kesalahan seperti itu sebelumnya. Hingga kini, lembaga adat sudah tidak bekerja lagi. Sejumlah kasus-kasus adat dibawa ke kepala desa, sehingga Kades merasa bebannya makin bertambah. Dalam pendekatan informal dengan Arifin, Kades berusaha untuk mendekati kembali lembaga adat agar kasus-kasus adat bisa diselesaikan lagi oleh lembaga adat. Lembaga adat sebagai forum pengadu di Tuva memang kurang didukung oleh berbagai forum lain. Meski ada dukungan migran seperti Arifin Panjaitan, seorang Batak, namun dukungan tersebut tidak signifikan secara kuantitatif. Jumlah migran dari etnis yang berkepentingan terhadap akses atas tanah jauh lebih besar. Jumlah tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap peta politik lokal di tingkat Desa. Dalam pemilihan 10 tahun terakhir, Kades selalu berasal dari migran yang sering kali tidak merujuk adat sebagai basis hukum tanah, tapi, sering kali mementingkan dirinya sendiri. Lihat Box 14. Box 14: Kepala Desa Dalam 10 Tahun Terakhir di Tuva Kepala Desa Agustinus T. Hikara adalah orang Toraja yang menjadi salah satu tokoh transaksi jual beli tanah di Tuva. Atas persetujuan Hikara pada tahun 2000, sebuah Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dari pengusaha kayu asal Palu, Saofan, beroperasi di Tuva. Izin tersebut dikeluarkan atas permintaan Tjalikoro, ketua Kelompok Tani Lalere Jaya yang menginginkan agar tanah mereka diberdayakan oleh Saofan untuk perkebunan kakao. Dalam praktik, IPKTM justu meluas hingga menebang hutan adat orang Sinduru. Saofan sendiri adalah seorang pengusaha sekaligus anggota LSM Yayasan Bantuan Hukum Rakyat di Palu. Dalam beberapa kesempatan, LSM ini mendukung Saofan secara hukum dan terlibat dalam lobi agar IPKTM yang dia peroleh tetap berjalan. Namun, tahun 2001, melalui desakan yang beruntun oleh lembaga adat Tuva dan jaringan LSM ke lembaga-lembaga pemerintah, sekaligus ancaman melaporkan Agustinus atas korupsi dana subsidi Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 30.600.000, maka Agustinus akhirnya menandatangani surat ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi agar mempertimbangkan kembali IPKTM yang diberikan ke Saofan karena praktiknya telah meresahkan warga (Dokumen LPA Awam Green). 27 Setelah periode Hikara, kades sekarang adalah Djumadil Suraila, orang Mandar. Menurut penuturan Arifin dan Mahori, Kades ini adalah orang yang dulu pernah dikenakan sanksi hukum adat. Dia masuk ke Tuva tahun 1970-an. Tapi karena melakukan pelanggaran serius yakni menebang kayu secara serampangan tanpa izin adat, oleh tetua adat Sinduru dia dikeluarkan dari Tuva. Tahun 1980-an dia masuk lagi ke Tuva dan mendapatkan lahan untuk bertani. Ketika terpilih sebagai Kades, bekas pembangkang ini menilai tidak tahu soal adat karena menurut dia, penduduk setempat menggunakan adat Kulawi. Sesuatu yang sangat berbeda karena adat Sinduru berbeda dengan Kulawi. 40 Pembubaran lembaga adat, menurut seorang tokoh adat, merupakan bentuk balas dendam Kades terhadap ketegasan aturan adat yang pernah dia alami. b. Lembaga Adat Bentukan NGO NGO merupakan forum lain yang diharapkan mendukung lembaga adat dan bisa menjadi fasilitator fungsi lembaga adat sebagai pengadu dan pengaduan. Pada tahun 2005, sebuah proyek TNC masuk. Program TNC adalah untuk membangun kesepakatan konservasi masyarakat. Salah satu output-nya adalah pembentukan Lembaga Konservasi di tingkat desa. Dalam studi Greg Acciaioli (2006) dipaparkan bahwa program ini bertujuan membangun kesepakatan konservasi dari masyarakat di pinggiran kawasan hutan, tidak melulu masyarakat adat tapi semua anggota masyarakat. Menurut Arifin dan Mahori, dulunya wilayah adat termasuk kawasan hutan terjaga dengan baik. Hampir tiap hari ada patroli rutin dari lembaga adat untuk menjaga agar tidak ada orang yang merambah kawasan Taman Nasional. Berdasarkan hasil KKM TNC dikeluarkan sejumlah tindak lanjut, antara lain memfasilitasi pembentukan lembaga konservasi di tingkat desa yang disebut Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam (BPSDA). Proses pembentukannya bergulir menggunakan sistem demokrasi modern (lihat Box 15). Penentuan para pengurusnya pun ditentukan berdasarkan kesepakatan mayoritas warga bersama Kepala Desa. Hasilnya, lembaga yang sejak awal dirancang untuk memperkuat konservasi versi tradisi masyarakat adat justru diisi oleh para pendatang. Lembaga ini diberi kepercayaan untuk mengkontrol kawasan konservasi menggantikan peran-peran adat. Sejak itu, lembaga adat minggir ke tepi dan melepaskan kontrolnya atas kawasan taman nasional. Beberapa NGO dan elite adat menilai, lepasnya kontrol adat menjadi awal semakin ditinggalkannya adat oleh para pendatang dan kawasan TN pun dibuka untuk kebun warga. Box 15: Harapan terhadap BPSDA Mahori, tokoh adat Tuva, sebetulnya berharap banyak terhadap BPSDA. Dia mendambakan kesepakatan yang tertuang dalam teks tersebut menjadi acuan untuk memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Karena itu, lembaga adat menyerahkan otoritas kawasan tersebut ke BPSDA dan hanya mengkontrol wilayah hutan adat sebelah barat Tuva yang merupakan hutan adat tersisa yang belum dimanfaatkan. Namun, ternyata kawasan itu diisi oleh para pendatang yang tidak sepenuhnya tahu hukum adat. Mahori mempunyai misi membuka kawasan hutan. Adat yang sejak lama mereka curigai tidak lagi menjadi acuan. Lembaga ini pun berjalan tanpa orientasi konservasi, bahkan beberapa anggotanya justru menjadi pionir pembukaan kawasan taman nasional. Alhasil, lembaga adat dalam 4 tahun terakhir tidak lagi memiliki peranan dalam mengatur dan mengawasi wilayah adat yang beririsan dengan kawasan taman nasional. BPSA yang dibentuk tidak menggantikan peran tersebut, sehingga sepenuhnya beralih ke Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu. Kehadiran BPSDA tidak menjadikan lembaga adat menjadi rujukan Balai Taman Nasional dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan 40 Djumadil Suraila, wawancara 28-2-2009, di Tuva. 28 kawasan Taman Nasional di wilayah Tuva. Melemahnya lembaga adat dan kembalinya kewenangan konservasi ke tangan Polhut, menurut tokoh-tokoh adat Sinduru, membuat posisi orang Sinduru sebagai minoritas menjadi kambing hitam dalam perambahan kawasan taman nasional. Kasus pemanggilan Sahrun adalah contoh konkret bahwa Sinduru akan menjadi target operasi kawasan taman nasional. Kesimpulan Kasus di Tuva dan Marena menunjukkan beberapa pelajaran penting dalam isu masyarakat adat dan lembaga adat. Pertama-tama, definisi masyarakat adat dalam praktiknya sangat beragam. Dalam studi atas dua komunitas adat ini, klaim masyarakat adat utamanya berbasis etnis yang merasa menjadi penghuni pertama suatu wilayah. Berbasis klaim tersebut, mereka mengembangkan klaimnya atas tanah, hukum, sejarah, lembaga politik dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks itu, peran lembaga adat menjadi sangat penting karena dari situ keluar otoritas yang mengendalikan dan menggunakan klaim adat. Namun peran lembaga adat didukung oleh berbagai aktor dan faktor. Lembaga adat akan kuat jika aktor-aktor seperti warga adat, migran, pemerintah, NGO mendukung fungsi lembaga adat. Dalam konteks masalah tanah, dukungan tersebut bisa hadir lewat pengakuan otoritas lembaga adat dalam mengurus wilayah adat. Di sisi lain, aktor juga bisa melemahkan lembaga adat bila pembangkangan atas putusan adat atau pengabaian atas lembaga adat membesar, terutama dalam jumlah. Kehadiran migran dalam jumlah besar yang merasa tidak perlu taat pada lembaga adat berpengaruh sangat signifikan terhadap eksistensi lembaga adat. Migran bisa menggunakan jumlahnya untuk memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan politik tingkat desa dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya di wilayah itu. Kekuasaan politik di tingkat desa sangat penting dalam menempatkan adat apakah diakui dalam kualitas tertentu atau sama sekali disingkirkan. Lebih dari itu, konsep masyarakat adat tampaknya akan kesulitan jika mengacu pada definisi “keaslian” karena percampuran masyarakat yang begitu rupa mengharuskan lembagalembaga adat bertoleransi untuk memberikan ruang bagi percampuran dalam berbagai bentuk, entah lewat perkawinan, sistem nilai bahkan hukum. Lembaga adat pun tidak lepas dari pengaruh, baik dalam hubungan dengan NGO, pemerintah maupun migran. Pengaruh-pengaruh itu sampai pada titik bahwa basis nilai dan hukum pembentukan dan operasionalisasi lembaga adat tidak lagi murni berasal dari suatu etnis tapi percampuran dari berbagai pengaruh. Menempatkan lembaga adat sebagai sesuatu yang murni tanpa pengaruh dari faktor dan aktor bertentangan dengan kenyataan bahwa masyarakat sudah berubah. Pada titik yang lain, pengaruh-pengaruh eksternal terhadap lembaga adat juga berdampak pada akses terhadap keadilan. Dalam kasus di Tuva, semakin tergerusnya peran lembaga adat juga menjadi awal semakin sulitnya orang Sinduru mengakses tanah. Lembaga adat yang memiliki peranan signifikan dalam pembagian tanah dibungkam oleh kehadiran institusi-institusi bentukan baru, baik dari negara maupun oleh NGO. Di situ, mempertimbangkan perlunya kehadiran lembaga adat juga berarti memberi kesempatan bagi kelompok yang minim akses untuk segera mendapatkan akses atas tanah. Contoh akses yang adil sudah diterapkan oleh lembaga adat Marena yang mendistribusikan tanah kepada semua warga Marena. Dalam praktik, lembaga adat Marena tidak lagi menggunakan konsep “asli” dan “tidak asli”, tapi cenderung mengakomodasi kepentingan semua warga. Di situ, adat memainkan peranan penting dalam menjamin akses semua warga atas tanah. 29 Referensi: Acciaioli, Greg 2006 ‘Environmentality Reconsidered: Indigenous To Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia’, makalah tidak diterbitkan, http://www.indiana.edu/~iascp/bali/papers/Acciaioli_Greg.pdf, diunduh pada 17-4-2009 di Jakarta. Anaya, S. James 1996 Indigenous Peoples in International Law, Oxford: Oxford University Press. Andasputra, Nico dan Julipin, Vincentius 1997 “Orang Kanayatnkah atau orang Bukit?”, dalam Nico Andasputra dan Vincentius Julipin (eds), Mencermati Dayak Kanayatn, hlm. 1-2. Pontianak: Institute of Dayakology Research and Development. Bedner, Adriaan dan Stijn van Huis 2008 “The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation”, Journal Bijdragen 164 (2/3). Bedner, Adriaan dan Jacqueline Vel 2009 “Akses Keadilan dan Rule of law (Negara Hukum)”,,Makalah Konsepsi No. 1: Jakarta: VVI. Davidson, James S. dan David Henley 2007 “Introduction: Radical Conservatism – The Protean Politics of Adat”, dalam James S. Davidson dan David Henley (eds), The Revival of Traditon in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism, hlm. 19. Routledge Contemporary Southeast Asia Series. Durning, Alan Thein dalam Lester R. Brown 1995 Masa Depan Bumi, hlm. 204-61. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Corntassel, Jeff J. dalam Christian Erni (ed) 2008 The Concept of Indigenous Peoples in Asia. A Resource Book, hlm. 56-7. IWGIA dan AIPP. Fakih, Mansour 1998 “Kata Pengantar” dalam Ton Dietz, Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik (Diterjemahkan oleh Roem Topatimasang dari Entitlements to Natural Resources: Countours of Political Environmental Geography. Utrecht: International Books. 1996). hlm. x-xi. Yogyakarta: INSISTPress. Roosa, John, Hilmar Farid dan Ayu Ratih (eds) 2004 Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Jakarta: ELSAM. Felstiner, William L. F., Richard Abel, Austin Sarat 1980/81 “The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming”, Law and Society Review 15-3/4:633. Haar, Ter 2001 Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, cetakan ketigabelas, Jakarta: Pradnya Paramita. Hollema, F.D. dalam Otje Salman Soemadiningrat 30 2002 Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Bandung: Alumni. ICRAF, AMAN, FPP 2003 Satu yang Kami Tuntut: Pengakuan. Jakarta: ICRAF, AMAN, FPP. IWGIA 2006 The Indigenous World, Denmark: Copenhagen. Li, Tania Murray 2007 The Will to Improve: Governmentality, Development and the Practice of Politics, Duke University Press. Mc Carthy, John 1999 “Village and State Regimes on Sumartra’s Forest Frontier. A Case from the Leuseur Ecosystem, South Aceh”, paper presented in the Resource Management in Asia Pasific Project Seminar Series, November 1999, hlm.3-4. Moniaga, Sandra 2002 “Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masalah Serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia 10-II (12 Juni 2002), Jakarta. Moniaga, Sandra 2003 “Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, di www.huma.or.id, hlm. 1, akses pada 10-1-2009. Prabowo, Wing 2006 Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Menurut Kebiasaan Masyarakat Adat Kulawi Moma, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Simarmata, Rikardo 2006 Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: UNDP. Sitorus, Felix 2002 “REVOLUSI COKELAT, Social Formation, Agrarian Structure, and Forest Margins in Upland Sulawesi, Indonesia”, STORMA Discussion Paper Series, Sub-program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 9 (November 2002), Research Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA). Van Vollenhoven, Cornelis 1987 Penemuan Hukum Adat (terj. dari De Ontdekking van het adatrecht, 1928). Jakarta: Djambatan. Zakaria, Yando 2000 Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Jakarta: Elsam. 31