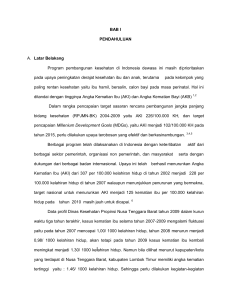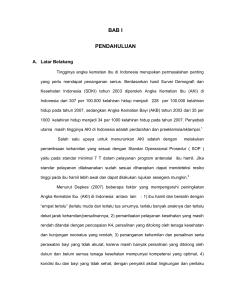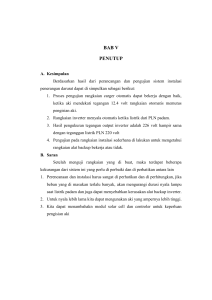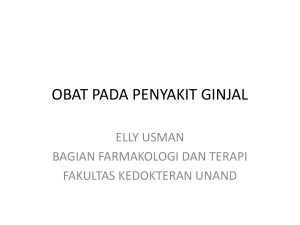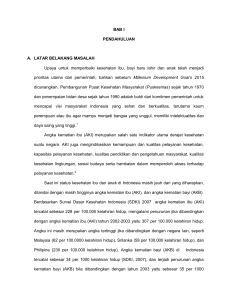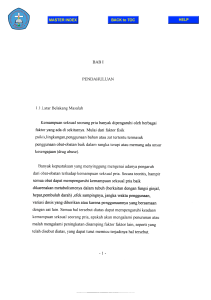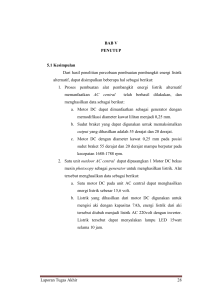BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Gagal Jantung Akut 2.1.1 Definisi
advertisement

4 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Gagal Jantung Akut 2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Gagal Jantung Akut Gagal jantung akut menurut European Society of Cardiology (ESC), merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi kegagalan fungsi jantung dengan awitan yang cepat maupun perburukan dari gejala dan tanda dari gagal jantung (McMurray et al, 2012). Hal ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan perhatian medis yang segera dan biasanya berujung pada hospitalisasi (Gheorghiade dan Pang, 2009). Pada sebagian besar kasus, gagal jantung akut terjadi sebagai akibat perburukan pada pasien yang telah terdiagnosis dengan gagal jantung sebelumnya (baik gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang rendah/ heart failure with reduced ejection fraction (HF-REF), maupun pada gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang masih baik/ heart failure with preserved ejection fraction (HF-PEF) (McMurray et al, 2012). Presentasi klinis dari gagal jantung akut biasanya merefleksikan spektrum kondisi, dan klasifikasinya memiliki batasan-batasan. Pasien dengan gagal jantung akut biasanya datang dengan salah satu dari keenam kategori klinis berikut (Filippatos, 2007, Pfister dan Schneider, 2009): Perburukan atau dekompensasi dari gagal jantung kronis/ADHF: biasanya terdapat riwayat perburukan dari gagal jantung kronis dalam pengobatan, dan bukti dari kongesti sistemik dan pulmoner. Tekanan darah rendah saat masuk biasanya berhubungan dengan prognosis yang jelek. Edema paru akut: pasien biasanya datang dengan distress pernafasan, takipneu dan ortopneu, ronki basah halus sering ditemukan di seluruh lapang paru. Saturasi oksigen arterial biasanya <90% dengan udara ruangan sebelum diberkan terapi oksigen. Gagal jantung akut hipertensif: tanda dan gejala dari gagal jantung yang disertai 4 peningkatan tekanan darah dan biasanya memiliki fraksi ejeksi ventrikel kiri yang masih baik. Terdapat bukti dari peningkatan tonus simpatis dan vasokonstriksi. Pasien mungkin dalam kondisi euvolemik atau hanya sedikit hipervolemik, dan datang dengan tanda-tanda kongestif paru tanpa disertai 5 kongesti sistemik. Respons terhadap terapi medis biasanya cepat, dan tingkat kematian dirumah sakit biasanya rendah. Renjatan kardiogenik (cardiogenic shock) didefinisikan sebagai bukti adanya hipoperfusi jaringan yang diinduksi oleh gagal jantung setelah dilakukannya koreksi adekuat dari preload dan aritmia mayor. Biasanya renjatan kardiogenik ditandai dengan penurunan tekanan darah (sistolik ≤90 mmHg, atau penurunan cepat dari rerata tekanan arteri >30 mmHg) disertai dengan oliguria atau anuria (<0.5 ml/kg /jam). Gangguan irama juga sering terjadi, dan bukti-bukti hipoperfusi organ serta kongesti paru biasanya terjadi secara cepat. Gagal jantung kanan teisolasi: ditandai dengan sindroma penurunan curah jantung (low output syndrome) tanpa adanya kongesti paru dengan peningkatan tekanan vena juguler, dengan atau tanpa hepatomegali dan tekanan pengisian ventrikel kiri yang rendah. Gagal jantung akut pada sindroma koroner akut: banyak pasien datang dengan gambaran klinis gagal jantung akut namun diserai bukti-bukti laboratorium dari sindroma koroner akut. Sekitar 15% pasien dengan sindroma koroner akut memiliki tanda dan gejala gagal jantung akut, dan episode gagal jantung akut tersebut biasanya berhubungan atau dipresipitasi oleh aritmia (bradikardia, fibrilasi atrium atau takikardi venrikel). 2.1.2 Patogenesis Gagal Jantung Akut Gagal jantung akut ditandai dengan abnormalitas hemodinamik dan neurohormonal yang buruk dan mungkin diakibatkan atau sebagai akibat dari jejas pada miokard dan atau ginjal. Abnormalitas tersebut mungkin dapat disebabkan karena iskemia, hipertensi, atrial fibrilasi atau penyebab non kardiak lainnya (seperti insufisiensi ginjal) atau sebagai akibat efek obat-obatan (Pfister dan Schneider, 2009). Beberapa mekanisme pathogenesis gagal jantung akut diantaranya adalah: Kongesti. Peningkatan tekanan diastolik ventrikel kiri akan berakibat kongesti pulmonal dan sistemik dengan atau tanpa curah jantung yang menurun merupakan presentasi utama pada mayoritas pasien dengan gagal jantung akut (Adams et al., 2005). Kongesti paru dapat didefinisikan sebagai hipertensi vena 6 pulmonalis (peningkatan tekanan baji kapiler paru/ pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)) dan akan berakibat edema interstisial dan alveolar paru. Kongesti sistemik bermanifestasi secara klinis dengan distensi vena jugularis dengan atau tanpa edema perifer dan peningkatan berat badan secara gradual sering ditemukan (Pfister dan Schneider, 2009). Biasanya, kongesti paru berat yang terjadi secara mendadak dipresipitasi oleh peningkatan tekanan darah (afterload), terutama pada pasien dengan disfungsi diastolik (Cotter et al, 2008). Gangguan ginjal, abmormalitas berat dari neurohormonal dan endothelial, gangguan diet dan beberapa obat-obatan seperti anti inflamasi non steroid (OAINS) juga berkontribusi terhadap kelebihan cairan (McMurray et al., 2012). Peningkatan tekanan diastolik ventrikel kiri yang tinggi, akan berkontribusi terhadap progresifitas dari gagal jantunglebih lanjut dengan aktivasi neurohormonal, iskemia subendokardial dan/ atau perubahan ukuran dan bentuk dari ventrikel kiri (remodelling) yang pada akhirnya berakibat pada insufisiensi katup mitral (Gheorghiade et al, 2006). Peningkatan tekanan vena sistemik (tekanan atrium kanan bagian atas), lebih sering disebabkan karena tekanan jantung kiri yang tinggi/ pulmonary capillary wedge pressure (PCWP), yang akan berkontribusi pada terjadinya sindroma kardio renal (SKR) (Mullens et al, 2008). Berat badan biasa digunakan sebagai penanda adanya kongesti pada scenario pasien gagal jantung yang dirawat inap maupun rawat jalan. Bagaimanapun, beberapa penelitian menyimpulkan hubungan yang kompleks antara berat badan, kongesti dan keluaran pasien dengan gagal jantung (Gheorghiade dan Pang, 2009). Cedera miokard. Pelepasan troponin sering terjadi pada kondisi gagal jantung akut, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner (Peacock et al, 2008). Hal ini nampaknya merefleksikan adanya cedera miokard, yang berhubungan dengan abnormalitas hemodinamik dan / atau neurohormonal atau sebagai akibat dari kejadian iskemia. Cedera juga bisa terjadi sebagai akibat tingginya tekanan diastolik ventrikel kiri, yang kemudian akan mengaktivasi stimulasi neurohormonal dan inotropik sehingga berakibat kepada ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen (Beohar et al, 2008). 7 Gangguan ginjal. Pada gagal jantung akut, abnormalitas ginjal akan menyebabkan retensi natrium dan air (Nohria et al, 2008). Gangguan struktural ginjal akibat hipertensi, diabetes dan arteriosklerosis merupakan penyebab yang sering ditemukan, dan perburukan fungsi ginjal terjadi pada sekitar 20-30% pasien yang dirawat dengan gagal jantung akut (Eren et al, 2012). Dari penelitian akhir, 20% pasien akan mengalami perburukan fungsi ginjal segera setelah pasien dipulangkan (Blair et al, 2008). Perburukan selama perawatan atau setelah pasien pulang mungkin diakibatkan karena penurunan curah jantung dan peningkatan tekanan vena, yang diperparah dengan pemberian diuretik dosis tinggi (Damman et al, 2007). Efek tidak langsung obat. Loop diuretik intravena merupakan agen lini pertama untuk meringankan gejala kongestif. Bagaimanapun, efek menguntungkan tersebut behubungan dengan abnormalitas elektrolit, aktivasi neurohormonal yang lebih lanjut dan perburukan fungsi ginjal. Pemberian loop diuretik intravena dengan dosis besar berhubungan dengan keluaran yang buruk pada pasien dengan gagal jantung. Namun, hal ini mungkin suatu penanda dari keparahan dari gagal jantung itu sendiri, dibandingkan dianggap sebagao penyebab peningkatan mortalitas (Hasselblad et al, 2007). Dobutamin, milrinon dan levosimendan akan meningkatkan profil hemodinamik, namun efek ini berhubungan dengan peningkatan tingkat konsumsi oksigen miokard (takikardia dan peningkatan kontraktilitas) dan hipotensi yang berhubungan dengan efek vasodilatasi (Mebazaa et al., 2007). Penurunan perfusi koroner yang berhubungan dengan hipotensi dalam kondisi peningkatan kebutuhan akibat akan mengakibatkan cedera miokard, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner (PJK) yang sering memiliki miokardium yang mengalami hibernasi atau iskemia (Beohar et al, 2008). Hipotensi yang berhubungan dengan penggunaan vasodilator mungkin juga mengakibatkan hipoperfusi miokardium dan ginjal dan kemungkinan dapat mengakibatkan cedera (Gheorghiade dan Pang, 2009). 2.1.3 Diagnosis Gagal Jantung Akut 2.1.3.1. Tanda dan gejala Banyak tanda-tanda gagal jantung yang terjadi akibat retensi air dan natrium yang biasanya akan membaik dengan cepat dengan pemberisan terapi 8 diuretik. Riwayat medis pasien juga pentning bagi penegakan diagnosis, dan gagal jantung tidak lazim terjadi pada pasien tanpa adanya riwayat medis yang relevan, misalkan riwayat infark miokard yang akan meningkatkan kemungkinan terjadinya gagal jantung pada pasien dengan tanda dan gejala yang khas (McMurray et al, 2012). Sekali diagnosis gagal jantung ditegakkan, sangatlah penting kemudian untuk menentukan penyebabnya, terutama penyebab yang dapat dikoreksi. Gejala dan tanda merupakan hal penting yang harus selalu dimonitor sebagai respon terapi dan tanda kestabilan pasien dengan gagal jantung. Gejala yang menetap pada pasien dengan terapi gagal jantungm biasanya menandakan perlunya terapi tambahan, dan perburukan gejala membutuhkan penanganan medis yang serius. Berikut merupakan tanda dan gejala gagal jantung menurut ESC yang dikeluarkan ditahun 2012 (McMurray et al, 2012). Tabel 2.1. Tanda dan gejala tipikal gagal jantung (McMurray et al, 2012). Tanda Tipikal Sesak napas Ortopneu Paroksismal nocturnal dispneu Penurunan toleransi aktivitas Kelelahan, letih dan kebutuhan waktu yang lebih banyak untuk istirahat setelah aktivitas Edema tungkai Kurang tipikal Batuk malam Mengi Peningkatan berat badan > 2kg/ minggu Penurunan berat badan (pada gagal jantung lanjut) Perasaan penuh Kurang nafsu makan Bingung (terutama pada usia tua) Depresi Palpitasi Sinkop Gejala Lebih spesifik Peningkatan JVP Reflek hepatojuguler Bunyi jantung 3 (gallop) Impuls apical yang bergeser kelateral Bising jantung Kurang spesifik Edema perifer (tungkai, skrotal) Krepitasi paru Efusi pleura Takikardia Pulsasi irregular Takipneu (>16 kali/ menit) Hepatomegali Asites Kakeksia 2.1.3.2. Uji Diagnostik Ekhokardiogram pemeriksaan penting dan untuk elektrokardiogram menegakkan (EKG) diagnosis merupakan gagal jantung. Ekhokardiogram menyajikan informasi yang segera mengenai volume ruang 9 jantung, fungsi sistoli dan diastolik ventrikel, ketebalan otot, dan fungsi katup (Paterson et al, 2011). Informasi ini penting dalam menentukan terapi yang pantas untuk pasien (misal penyekat angiotensin converting enzyme (ACE) dan penyekat beta untuk disfungsi sistolik atau operasi untuk stenosis aorta). EKG membantu untuk melihat irama jantung dan konduksi elektrik, misal adanya penyakit sinoatrial, blok atrioventrikuler, atau konduksi interventrikuler yang abnormal. Temuan ini juga penting untuk menentukan penatalaksanaan (seperti kontrol irama untuk pasien dengan fibrilasi atrium, pemacuan untuk bradikardia, dan terapi resinkronisasi jantung untuk pasien dengan left bundle branch block (LBBB)). EKG juga menunjukkan bukti adanya hipertrofi ventrikel kiri atau gelombang Q yang mengindikasikan adanya kehilangan miokardium yang viabel, yang membantu memberikan bukti tentang kemungkinan etiologi dari gagal jantung (McMurray et al, 2012). Informasi yang disajikan oleh 2 pemeriksaan ini sudah mampu untuk menegakkan diagnosis kerja dan perencanaan manajemen bagi mayoritas pasien. Pemeriksaan biokimiawi dan hematologi rutin juga penting, sebagai bagian apakah penyekat sistim renin angiotensin aldosterone (SRAA) dapat dimulai secara aman (dengan pemeriksaan fungsi ginjal dan kalium) dan untuk mengekslusi adanya anemia (yang mirip atau dapat memperburuk gagal jantung). Pemeriksaan penunjang lain secara umum hanya diperlukan bila diagnosis belum bias ditegakkan (misal bila gambaran ekhokardiografi suboptimal, atau jika terdapat kausa gagal jantung yang tidak umum) atau jika ada indikasi untuk mengevaluasi lebih jauh penyebab yang mendasari masalah jantung pasien (misal pencitraan perfusi atau angiografi pada pasien dengan kecurigaan PJK atau endomiokardial biopsi pada beberapa penyakit miokard) (McMurray et al, 2012). 2.1.3.3. Peptida natriuretic Karena tanda dan gejala gagal jantung kadang tidak spesifik, banyak pasien yang dicurigai mengalami gagal jantung yang dikirim menjalani pemeriksaan ekhokardiografi, namun ternyata tidak memiliki abnormalitas dalam struktur jantung. Ketka kemampuan ekhokardiografi menjadi terbatas, pendekatan lain untuk mendiagnosis adalah dengan memeriksa konsentrasi peptida natriuretik darah, keluarga hormon yang disekresikan berlebih bila terjadi jejas pada jantung atau beban pada salah satu ruang jantung mengalami 10 peningkatan (misal pada fibrilasi atrium, emboli paru dan beberapa kondisi nonkardiak termasuk gagal ginjal) (Ewald et al, 2008). Kadar peptida natriuretik juga akan meningkat seiring dengan usia, namun dapat menurun pada pasien dengan obesitas (Daniels et al, 2006). Kadar peptida natriuretik yang normal pada pasien yang belum tertangani secara nyata mengeksklusi adanya penyakit jantung, yang akan menyebabkan pemeriksaan ekhokardiografi tidak diperlukan lagi (investigasi penyebab non-kardiak mungkin lebih produktif pada pasien ini) (Maisel et al, 2008). Banyak penelitian telah meneliti batas konsentrasi dua untuk mengeksklusi gagal jantung untuk dua macam peptida natriuretik yang biasa digunakan, B-type natriuretic peptide (BNP) dan N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP). Batasan eksklusi berbeda pada pasien yang dating dengan awitan akut atau perburukan gejala dan pada psein dengan awitan yang lebih gradual. Untuk pasien dengan awitan akut atau perburukan gejala, nilai optimal untuk mengeksklusi adalah 300 pg/mL untuk NT-pro BNP dan100 pg/mL untuk BNP. Untuk pasien non akut, nilai optimal untuk mengeksklusi adalah 125 pg/mL untuk NT-proBNP dan 35 pg/mL untuk BNP. Sensitifitas dan spesifisitas dari BNP dan NT-proBNP untuk diagnosis gagal jantung juga lebih rendah pada pasien-pasien non akut (McMurray et al, 2012). 2.1.3.4. Foto Toraks Foto toraks memiliki keterbatasan dalam penegakan diagnosis dari pasien dengan kecurigaan gagal jantung. Hal ini mungkin sangat berguna dalam mengidentifikasi alternatif keterlibatan paru untuk tanda dan gejala pasien. Pemeriksaan ini akan menunjukkan kongesti vena pulmonalis atau edema pada pasien dengan gagal jantung. Penting untuk dicatat bahwa disfungsi sistolik ventrikel kiri yang signifikan akan memberikan gambaran kardiomegali pada foto thoraks (McMurray et al, 2012). 2.1.3.5. Pemeriksaan Rutin Laboratorium Sebagai tambahan untuk pemeriksaan biokimiawi (natrium, kalium, kreatinin, laju filtrasi gromerolus/ estimated glomerular filtration rate (eGFR)) dan hematologis standar (hemoglobin, hematocrit, ferritin, leukosit dan platelet), sangatlah berguna untuk memeriksa kadar hormon penstimulasi tiroid, dikarenakan penyakit tiroid dapat menyerupai atau memperburuk gagal jantung. Kadar gula darah juga penting untuk diperiksa dalam penegakkan ddiagnosis 11 diabetes pada pasien gagl jantung. Enzim hati juga biasa ditemukan tidak normal pada pasien dengan gagal jantung, juga pentung untuk pengambilan keputusan yang menyangkut terapi amiodaron dan warfarin (McMurray et al, 2012). 2.2 Cedera Ginjal Akut pada Gagal Jantung Akut 2.2.1. Sindroma Kardio Renal Banyak pasien yang datang kerumah sakit dengan menderita gangguan jantung dan ginjal dalam berbagai tingkat keparahan. Interaksi antara organ tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hemodinamik seperti pengaturan volume darah dan tonus vaskuler. Ganguan utama salah satu dari kedua organ ini akan menghasilkan disfungsi atau jejas sekunder pada organ lainnya. Interaksi tersebut merepresentasikan sebuah dasar patofisiologi untuk sebuah entitas klinis yang biasa disebut dengan sindroma kardiorenal (SKR) (Ronco et al, 2008b) Walaupun secara umum didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai dengan inisiasi dan/ atau progresifitas dari insufisiensi ginjal sebagai akibat sekunder dari gagal jantung, istilah SKR juga digunakan untuk mendiskripsikan efek negatif akibat berkurangnya fungsi ginjal pada jantung dan sistem sirkulasi (Ronco et al, 2008c). Ronco dan kawan-kawan pada tahun 2008 (Ronco et al, 2008a), telah membagi SKR berdasarkan kejadian alamiah terjadinya interaksi bidireksional antara jantung dan ginjal menjadi 5 subtipe yang merefleksikan patofisiologi sesuai alur waktu dari disfungsi jantung dan ginjal yang konkomitan. Secara umum, SKR dapat didefinisikan sebagai gangguan patofisiologis dari jantung dan ginjal, dimana disfungsi akut ataupun kronis salah satu organ tersebut dapat menginduksi disfungsi akut atau kronis organ yang lain. SKR tipe 1 merefleksikan perburukan mendadak fungsi jantung (misal pada renjatan kardiogenik dan ADHF yang mengakibatkan cedera ginjal akut AKI. SKR tipe 2 merupakan abnormalitas kronis jantung (misal pada gagal jantung kongestif kronik) yang menyebabkan gagal ginjal kronis progresif. SKR tipe 3 merupakan perburukan fungsi ginjal yang mendadak yang menyebabkan disfungsi jantung akut, seperti aritmia, iskemia dan gagal jantung. SKR tipe 4 dideskripsikan sebagai kondisi gagal ginjal kronis yang berkontribusi kepada penurunan fungsi, hipertrofi jantung dan/ atau peningkatan resiko dari kejadian kardiovaskuler. Sedangkan SKR tipe 5 adalah kondisi sistemik (misal: sepsis) yang menyebabkan disfungsi jantung dan ginjal secara bersamaan. 12 2.2.2. Sindroma Kardiorenal Tipe 1 Sindroma kardio renal tipe 1 paling sering didapatkan pada pasien dengan ADHF kemudian mengikuti kejadian iskemik (bedah jantung, infark miokard) dan non iskemik (disfungsi katup, diseksi aorta, emboli paru, dsb) dari jantung (Eren et al, 2012). Lebih dari 40% dari pasien yang dirawat dengan ADHF akan mengalami AKI (Bagshaw et al, 2010). Pasien–pasien tersebut memerlukan manajemen yang lebih kompleks dikarenakan tingginya angka mortalitas (Haase et al, 2013). Mekanisme klasik dari SKR tipe 1 adalah penurunan curah jantung dan aktivasi neurohormonal serta pelepasan substansi vasoaktif yang mengakibatkan rendahnya perfusi ke ginjal dan kemungkinan iskemia ginjal. Sebagai tambahan, tingginya tekanan vena sentral, akan mengakibatkan peningkatan tekanan intra abdomen yang kemudian mengakibatkan kongesti vena, aktivasi dari sistem saraf simpatis dan SRAA serta pelepasan substansi vasoaktif lain seperti endotelin, Anemia dan gangguan sistem imun dan komunikasi antar sel somatik yang bermakna juga berkontribusi secara bermakna terhadap terjadinya AKI (gambar 1) (Haase et al, 2013). Gambar 2.1. Mekanisme, korelasi histologi, biomarker dan keluaran dari SKR tipe 1 pada gagal jantung dekompensasi akut. ADHF = Acute decompensated heart failure; AKI = acute kidney injury (istilah AKI meliputi istilah ‘WRF’, ‘worsening renal function/ perburukan fungsi ginjal yang biasanya didefinisikan 13 peningkatan kreatinin serum dua kali lipat); AMI = acute myocardial infarction; PE = pulmonary embolism; SVR = systemic vascular resistance; HF = heart failure; CKD = chronic kidney disease; RAS = renal artery stenosis; GFR = glomerular filtration rate; NGAL = neutrophil gelatinase-associated lipocalin; IL18 = interleukin-18; KIM-1 = kidney injury molecule 1; L-FABP = liver-type fatty acid binding protein; NAG = N-acetylglucosamine (Haase et al, 2013). Observasi dari beberapa percobaan dan penelitian klinis menyatakan bahwa mekanisme hemodinamik memainkan peranan utama pada patofisiologi SKR tipe 1 pada kasus ADHF. Beberapa percobaan dengan hewan coba menunjukkan adanya kejadian hemodinamik inisial pada SKR tipe 1 akan menyebabkan penurunan aliran darah arterial ginjal, konsumsi oksigen ginjal, laju filtrasi glomerulus/ glomerular filtration rate (GFR) dan peningkatan resistensi vaskuler ginjal, namun kemampuan untuk mengkontra hemodinamik secara aktif seperti pengalihan perfusi darah selektif menuju ginjal akan mengembalikan parameter-parameter hemodinamik dan fungsi ginjal menuju normal kembali (Hanada et al, 2012). Pada gagal jantung dekompensasi akut secara umum, pendekatan melaui profil hemodinamik yang berbeda berdasarkan penilaian klinis telah diterapkan pada pasien-pasien secara individual. Pendekatan ini terdiri dari kategorisasi pasienpasien yang bergantung pada profil hemodinamik sistemiknya, termasuk kecukupan perfusi (penurunan curah jantung dan volume cairan tersirkulasi efektif) dan juga derajat kongestif paru (peningkatan tekanan vena sentral atau tekanan baji arteri pulmoner). Hal-hal tersebut, dapat saling dikombinasikan menjadi empat profil hemodinamik yang terdiri dari basah atau kering dan hangat atau dingin (gambar 2) (Stevenson dan Perloff, 1989). Baik Terganggu Perfusi sistemik 14 Kering dan hangat Basah dan hangat RBF secara diskonkordan tekanan vena ginjal Disregulasi mikrovaskular RBF secara diskonkordan intrarenal Gangguan autoregulasi Kering dan dingin Basah dan dingin RBF RBF Gangguan autoregulasi tekanan vena ginjal Gangguan autoregulasi Tidak Ya Kongesti Paru Gambar 2.2. Profil hemodinamik sistemik pada pasien ADHF dan konsekuensinya pada hemodinamik ginjal di SKR tipe 1 (Stevenson LW and JK, 1989). Gambar ini merupakan kombinasi profil hemodinamik sistemik pada ADHF dengan mekanisme hemodinamik ginjal yang dapat menyebabkan SKR tipe 1 pada masing-masing profilnya. Pada profil dingin, AKI dapat terjadi sebagai konsekwensi dari penurunan aliran darah ginjal/ renal blood flow (RBF) ketika sistem autoregulasi gagal untuk mempertahankan laju filtrasi glomerulus. Pada profil basah, peningkatan tekanan vena sentral akan meningkatkan tekanan vena ginjal, yang akan mengurangi tekanan perfusi ginjal, meningkatkan tekanan interstisial ginjal, dan melawan tekanan filtrasi sehingga menyebabkan kolaps tubulus. Pada profil hangat, walaupun perfusi sistemik relatif terjaga, RBF berkurang secara diskonkordan, sebagai akibat gangguan autoregulasi (contoh: penghambatan sistem RAA, aktivasi sistem saraf simpatis yang berlebihan), berkurangnya mekanisme umpan balik tubuloglomerular (missal sebagai akibat dari obat anti inflamasi non steroid (OAINS)), stenosis arteri ginjal atau kondisi predisposisi yang menyebabkan hilangnya nefron. Yang perlu dicatat, gangguan atau berkurangnya autoregulasi mungkin memainkan peran kunci, yang berakibat penurunan tekanan perfusi ginjal. Mengingat sebagian besar pasien ADHF memiliki hipertensi, jika SKR tipe 1 terjadi sebagai akibat dari penurunan RBF (dan/ atau penurunan tekaknan perfusi ginjal), hal ini setidaknya berkontribusi pada disfungsi autoregulator tubuh (Haase et al, 2013). Acute kidney injury merupakan gabungan beberapa kondisi yang mempengaruhi struktur dan fungsi ginjal. AKI didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba yang termasuk didalamnya, tapi tidak terbatas pada gagal ginjal akut. Hal ini mencakup gejala klinis yang luas termasuk penyakit ginjal yang speisfik (misal, nefritis interstisial akut, penyakit glomerular dan vasculitis ginjal akut), kondisi non spesifik (misal, iskemia, cedera akibat toksik), dan gangguan patologi ekstra renal (misal, azotemia prerenal dan nefropati obstruktif akut postrenal). Lebih dari satu kondisi ini mungkin dapat terjadi secara bersamaan pada pasien yang sama, namun yang lebih penting, bukti epidemiologis mendukung, walaupun kecil, AKI yang reversibel, memiliki konsekwensi klinis yang penting, termasuk peningkatan risiko kematian (Hoste et al, 2006). Lebih jauh, karena manifestasi dan konsekwensi klinis 15 AKI dapat sangat mirip tanpa memandang etiologi, sindroma AKI mencakup baik cedera langsung ke ginjal maupun gangguan akut pada fungsi ginjal (Kellum et al, 2012). 2.2.3. Definisi dan Staging AKI Acute kidney injury merupakan masalah kesehatan yang sering ditemukan, berbahaya dan berpotensi untuk disembuhkan. Walaupun hanya terjadi sedikit penurunan fungsi ginjal sudah dapat memberikan prognosis yang buruk. Deteksi dini AKI mungkin dapat meningkatkan keluaran pasien. Dua definisi AKI yang berdasar kreatinin serum dan output urin (stratifikasi Risk, Injury, Failure, Loss and End state renal disease (RIFLE) (gambar 2.3) dan kriteria menurut Acute Kidney Injury Network (AKIN) (tabel 2.2)) telah diperkenalkan dan divalidasi (Mehta, et al, 2007). Secara umum, AKI didefinisikan sebagai (1) peningkatan kreatinin serum ≥ 0.3 mg/dL (≥ 26.5μmol/L) dalam kurun waktu 48 jam atau (2) peningkatan kreatinin serum ≥ 1,5 kali dari garis dasar, yang diketahui atau diasumsikan terjadi dalam kurun waktu 7 hari terakhir, atau (3) volume urin ≤ 0,5 ml/kg/ jam selama 6 jam (Kellum et al., 2012). Tabel 2.2. Kriteria AKI menurut klasifikasi AKIN (Mehta, et al, 2007). Stadium 1 2 3 Kreatinin serum 1,5-1,9 kali dari awal Atau Peningkatan ≥0,3 mg/dL (≥26,5 μmol/ L) 2,0-2,9 kali dari awal 3,0 kali dari awal Atau Peningkatan kreatinin serum ≥ 4,0mg/dL (≥353,6 μmol/L) Atau Penggunaan renal replacement therapy/ CRRT Atau pada pasien <18 tahun, dengan penurunan eGFR hingga <35 mL/min per 1,73 m2 Urin output <0,5 mL/kg/jam selama 6-12 jam <0,5mL/kg/jam selama ≥12 jam < 0,3 mL/kg/jam ≥12 jam Atau Anuria selama >12 jam 16 Gambar 2.3. Kriteria AKI menurut klasifikasi RIFLE (Kellum et al., 2012) 2.3. Manajemen gagal jantung akut: fokus pada loop diuretik 2.3.1. Loop diuretik Obat-obatan diuretik berfungsi untuk mempengaruhi fisiologi ginjal untuk meningkatkan produksi urin dan ekskresi sodium yang lebih bermakna (natriuresis). Diuretik telah lama digunakan untuk manajemen gagal jantung simtomatik dengan retensi cairan, sebagai tambahan terapi standar seperti ACEi. Dalam kasus hipertensi, diuretik direkomendasikan untuk terapi lini pertama, terutama setelah sebuah uji meta analisis menemukan bahwa diuretik dosis rendah merupakan terapi paling efektif sebagai lini pertama untuk mencegah komplikasi kardiovaskuler (Psaty, 2003). Loop diuretik ditemukan pada tahun 1960an disaat para peneliti mengembangkan obat pengganti yang lebih efektif bagi diuretik organik yang mengandung merkuri. Furosemide, loop diuretik yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat, merupakan jenis diuretik yang pertama kali dikembangkan, yang kemudian diikuti oleh bumetanide dan torsemide (Ernst, 2013). Derivat sulfonamide ini merupakan loop diuretik paling standar untuk penatalaksanaan gagal jantung kongestif berat, bahkan, furosemide mampu mengurangi sesak napas walalupun belum terjadi diuresis dan hal ini dikarenakan adanya efek venodilatasi dan penurunan preload (Oppie dan Kaplan, 2009). Seluruh loop diuretik, bekerja dengan berikatan pada kotransporter Na+-K+-2Cl pada bagian tebal lengkung Henle ascenden. Segmen ini bertanggung jawab untuk mengkonsentrasikan urin, dan pengangkatan solute dari area ini akan menghasilkan cairan interstisium medulla ginjal yang hipertonis, yang berfungsi sebagai kekuatan osmotik sehingga akan terjadi reabsorrbsi air pada duktus kolektivus. Penghambatan 17 proses reabsorbsi dengan loop diuretik inilah yang akan mengganggu kemampuan ginjal untuk menghasilkan urin terkonsentrasi yang menyebabkan natrium klorida dan ion kalium tetap berada intralumen dan akan hilang didalam urin (Ernst, 2013). Selain itu, furosemide memiliki efek venodilatasi yang bertujuan untuk mengurangi preload pada gagal jantung kiri akut dalam waktu 5 hingga 15 menit, mekanisme yang mendasari hal ini kemungkinan, terjadi akibat kejadian ikutan paska vasokonstriksi reaktif (Oppie dan Kaplan, 2009). 2.3.2. Farmakokinetik Seluruh loop diuretik secara umum berikatan dengan albumin serum (>95%), dan sebagai konsekwensinya, untuk mendapat akses menuju tempat aksinya, loop diuretik harus melalui sekresi aktif meuju lumen tubulus melalui transporter anion organik probenecid-sensitif yang berlokasi di tubulus proksimal. Proses ini mungkin akan menjadi lambat pada kondisi dimana terjadi peningkatan asam organik endogen seperti pada GGK dan penggunaan obat-obatan yang juga mengginakan transporter yang sama, diantaranya salisilat dan OAINS (Ernst, 2013). Bioavailabilitas, waktu paruh, dan rute metabolism berbeda antara masingmasing duretik lengkung Henle yang tersedia. Furosemide, yang paling banyak digunakan, memiliki profil farmakokinetik yang kurang baik diantara loop diuretik yang lain, absorbsinya bervariasi diantara 10-100% dan penggunaan bersamaan dengan makanan akan lebih menurunkan bioavailabilitasnya, sangat berbeda bila dibandingkan absorbsi bumetanide dan torsemide yang mampu mencapai 80100%. Furosemide memiliki permulaan aksi yang cepat dengan waktu paruh sekitar 1,5 jam. Respons terapi akan terjadi dalam hitungan menit etelah pemberian intravena, sedangkan furosemide peroral respons puncaknya terjadi pada 30-90 menit. Efek diuresis akan berlanjut hingga 2-3 jam dan bertahan hingga 6 jam. Karena aksinya yang singkat, pada pemberian loop diuretik dapat terjadi periode antinatriuresis yang signifikan setelah bioavailabilitasnya lebih rendah dibanding ambang batas dosis untuk memicu diuresis. Kejadian rebound retensi natrium paska dosis inilah yang menyebabkan furosemide dan bumetanide harus diberikan beberapa kali dalam sehari untuk memastikan terdapat jumlah obat yang optimal pada tempat aksinya (Ernst, 2013). 18 Furosemide diekskresikan tanpa mengalami perubahan (sebesar 50%) dan sisanya akan terkonjugasi menjadi asam glukoronat di ginjal. Insufisiensi ginjal, akan menganggu farmakokinetik furosemide dengan memperpanjang waktu paruh palsma dan durasi aksi yang diakibatkan karena terganggunya ekskresi melalui urin dan konjugasi di ginjal (Ernst, 2013). 2.3.3. Farmakodinamik Perubahan hemodinamik spesifik pada mikrosirkulasi sistemik dan ginjal terjadi setelah pemberian loop diuretik. Pertama-tama, pemberian secara intravena akan menstimulasi SRAA di makula densa, yang akan mengakibatkan vasokonstriksi, peningkatan afterload, dan penurunan aliran darah ginjal. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya rspons terhadap dosis inisial. Respons fase kedua akan terjadi pada 5-15 menit setelahnya dan ditandai dengan peningkatan pelepasan vasodilator prostaglandin oleh ginjal, yang akan menyebabkan venodilatasi dan penurunan preload dan tekanan pengisian ventrikel, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbaikan gejala walaupun efek diuresis belum tejadi. Dengan pemberian furosemide jangka panjang, akan terjadi proses adaptasi kronis yang dikenal sebagai efek “braking”, perubahan ini merupakan kompensasi alami dalam menjaga volume intravaskuler, yang kemudian akan menyebabkan toleransi terhadap efek diuretik. Toleransi diuretik harus dibedakan secara klinis dari resistensi diuretik yang lebih tepat merujuk pada yang terjadi bersamaan dengan kondisi patologis seperti gagal ginjal, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif dan sirosis (Ernst, 2013). 2.3.4. Dosis Dosis diuresis tergantung pada pencapaian ambang diuretik dan spesifik pada masing-masing pasien. Sekali ambang dosis dilewati, akan terjadi rerata optimal dari hantaran obat yang berujung pada respons maksimal. Karena respon diuretik tidak secara linear berhubungan dengan dosis, sekali dosis dan rerata hantaran telah ditentukan dan mencapai respon maksimal, penambahan pemberian diuretik tidak akan meningkatkan efek diuresis (Ernst, 2013). Furosemide intravena biasanya dimulai dengan dosis bolus inisial 40mg (tidak boleh melebihi 4mg/menit untuk mengurangi resiko ototoksisitas). Saat fungsi ginjal terganggu, seperti pada usia lanjut, dosis yang lebih tinggi mungkin dibutuhkan, dan dosis yang lebih tinggi lagi 19 pada gagal ginjal dan gagal jantung kronis yang berat. Furosemide oral memiliki rentang dosis yang lebih lebar (20-240mg/ hari atau lebih), dikarenakan absorbsi obat yang sangat bervariasi 10%-100% (rata-rata 50%). Pada keadaan oliguria yang tidak disebabkan karena kekurangan cairan dan GFR kurang dari 20ml/menit, dosis furosemide dapat ditingkatkan dari 240mg hingga 2000mg, hal ini mungkin diperlukan karena menurunnya ekskresi luminal (Oppie dan Kaplan, 2009). 2.3.5. Furosemide pada Gagal Jantung Akut Diuretik sangat berguna pada manajemen jangka panjang pasien dengan gagal jantung kronis stabil yang memiliki kecenderungan pola penambahan berat badan secara terus menerus (kelebihan cairan) walaupun telah patuh dengan diet rendah natrium. Diuretik juga berguna pada pasien dengan ADHF dimana furosemide merupakan komponen kritikal yang harus ada pada manajemen tata laksana. Gagal jantung ringan, biasanya memiliki respon yang menjanjikan terhadap diet rendah natrium (50-100 mmol/ hari) dan diuretik tiazid dosis rendah. Namun, saat terjadi perburukan gagal jantung, GFR juga akan mengalami penurunan dan pasien akan kurang responsive terhadap dosis konvensional diuretik tiazid, yang biasanya terjadi saat GFR <30 mL/menit. Dosis loop diuretik yang lebih besar dan frekuen, ditunjang dengan diet rendah natrium yang ketat mungkin diperlukan pada pasien dengan gagal jantung yang progresif (Sicca, 2012). Karena adanya gangguan pada farmakokinetik dan farmakodinamik diuretik, pasien dengan gagal jantung biasanya memiliki resistensi terhadap obat-obatan diuretik. Resistensi diuretik pada evaluasi pasien gagal jantung dapat dilakukan dengan penghitungan intake natrium dan air dalam diet harian. Yang cukup penting dalam menegakkan diagnosis resistensi diuretik adalah memastikan kapatuhan pasien dalam meminum dosis obat diuretik, dan pasien tidak meminum obat yang dapat menganggu aksi dari diuretik seperti OAINS (Sicca, 2012). Walaupun telah banyak pengalaman klinis penggunaan furosemide dalam kasus gagal jantung, data prospektif untuk penggunaannya tidaklah kuat, dan panduan terbaru gagal jantung hanya berdasarkan opini para ahli (Yancy et al, 2013, McMurray et al, 2012). Sebagai hasilnya, praktek klinis dilapangan sangatlah bervariasi tanpa memandang jalur pemberian dan dosis. Loop diuretik dosis tinggi mungkin memiliki efek yang membahayakan, termasuk aktivasi dari 20 SRAA, sistem saraf simpatis, gangguan elektrolit dan perburukan fungsi ginjal (Felker et al, 2009). Sebagai tambahan beberapa studi obervasional juga telah menunjukkan hubungan antara diuretik dosis tinggi dan keluaran klinis yang tidak diinginkan, termasuk gagal ginjal, progresifitas gagal jantung dan kematian. Beberapa observasi memang saling tumpang tindih, apakah diuretik dosis tinggi lebih merujuk sebagai penanda keparahan penyakit yang lebih berat atau lebih kepada mediator terjadinya efek yang tidak diinginkan (Felker et al, 2011). Gambar 2.4. Kurva Kaplan-Meier untuk gabungan titik akhir klinis dari kematian, rehospitalisasi, atau kunjungan perawatan gawat darurat dalam jangka waktu 60 hari, pasien yang mendapatkan bolus tiap 12 jam disbanding dengan pasien degan pemberian kontinyu (panel A) dan pada grup yang mendapatkan dosis rendah diuretik (ekuivalen dengan dosis harian pasien) disbanding dengan kelompok yang mendapat diuretik dosis tinggi (2.5 kali dosis oral harian) (panel B) (Felker et al, 2011). Selain ketidakpastian dosis, pemberian furosemide pada ADHF juga mengalami ketidakpastian dalam metode pemberian yang paling optimal. Data farmakologis dan farmakodinamik menyatakan bahwa ada keuntungan potensial dari pemberian intravena secara kontinyu bila dibandingkan dengan bolus intermiten. Pada keadaan yang tidak menentu ini, Birhan Yilmaz dan kawan-kawan ditahun 2011 (Yilmaz et al, 2011), telah meneliti efek dosis terhadap kematian jangka pendek, dan tidak didapatkan perbedaan signifikan terhadap keluaran pada pemberian dosis tinggi (>1mg/ kg/ 24 jam) dibanding pada pemberian dosis rendah. National Heart, Lung, and Blood Institute juga telah melakukan sebuah studi untuk mengevaluasi strategi optimalisasi diuretik pada pasien ADHF dihubungkan dengan keluaran jangka panjang terhadap keluaran klinis dan penanda fungsi ginjal dan tidak ditemukan perbedaan signifikan baik pada pemberian diuretik bolus 21 intermiten atau kontinyu dan pemberian dosis tinggi maupun dosis rendah (gambar 2.4) (Felker et al, 2011). 2.4. Penanda Biokimiawi Acute Kidney Injury Disfungsi ginjal merupakan kejadian yang sering terjadi pada pasien gagal jantung dan merupakan faktor prognostik bebas yang kuat dalam menilai kejadian yang tidak diinginkan (Smith et al., 2006). Prevalensinya meningkat pada pasien yang datang dengan gagal jantung yang lebih berat. Hospitalisasi pada pasien dengan gagal jantung akut berhubungan dengan perburukan fungsi ginjal lanjut pada 3050% pasien, dan hal ini berhubungan dengan pemanjangan lama rawat inap, peningkatan biaya kesehatan dan kejadian rawat ulang, serta kematian setelah pasien pulang (Marco et al, 2008). Pada tahun 2012, sebuah penelitian yang dilakukan Breidthardt dan kawan-kawan, kejadian AKI sudah mulai terjadi sejak pasien masuk perawatan gawat darurat pada sekitar sepertiga pasien dengan ADHF yang akan terdeteksi saat pasien dirawat dirumah sakit. Sekitar 50% pasien dengan AKI tersebut akan memenuhi kriteria AKI dalam waktu 48 jam pertama dirumah sakit, dan hanya minoritas yang akan mengalami AKI setelah 48 jam (gambar 2.5) (Breidthardt et al, 2012). Gambar 2.5. Grafik waktu kejadian AKI pada kondisi gagal jantung dekompensasi akut (Breidthardt et al, 2012). 2.4.1. Kreatinin Serum Diagnosis dari AKI biasanya didasari baik dari peningkatan kreatinin serum atau deteksi adanya oliguria. Menurut kriteria AKIN (Kellum et al., 2012), AKI didefinisikan sebagai peningkatan kadar kreatinin serum ≥ 0.3 mg/dL dalam waktu 48 jam, atau peningkatan kadar kreatinin serum ≥ 1,5 kali dari awal dalam jangka waktu 7 hari perawatan, atau produksi urin < 0.5 cc/ kg berat badan perjam selama 6 jam. Kreatinin serum merupakan penanda yang buruk dalam mendeteksi disfungsi 22 ginjal tahap awal, dikarenakan konsentrasi serum sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor non ginjal, seperti berat badan, ras, usia, jenis kelamin, volume total tubuh, obat-obatan, metabolism otot dan intake protein (Coca et al, 2008). Penggunaan kreatinin serum bahkan lebih buruk dalam mendeteksi AKI, dikarenakan pasien tidak dalam kondisi basal, kreatinin serum akan jauh lebih tertinggal setelah terjadinya cedera ginjal. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar kreatinin serum tidak mampu dimonitor hingga 48 -72 jam paska terjadinya kerusakan awal di ginjal. Sebagai tambahan, penyakit ginjal signifikan dapat terjadi dengan perubahan kreatinin yang minimal atau bahkan tidak mengalami perubahan, dikarenakan karena adanya kemampuan ginjal untuk meningkatkan sekresi tubular dari kreatinin, atau faktor-faktor lain (Coca et al, 2008). Sebuah penanda biokimiawi dari AKI yang mudah untuk dihitung, tidak terpengaruh oleh variabel biologis lain, dan memungkinkan untuk dilakukannya deteksi dini dan stratifikasi resiko akan sangat membantu dalam penegakan diagnosis AKI. American Society of Nephrology telah menetapkan pengembangan penanda biokimiawi sebagai pendeteksi dini kejadian AKI sebagai prioritas. Beberapa penanda biokimiawi AKI telah berhasil diidentifikasi selama beberapa tahun terakhir dimana dapat meningkat pada kondisi cedera iskemia ginjal baik pada hewan coba maupun pada manusia dengan klinis AKI (Coca et al., 2008). Kemampuan penanda biokimiawi untuk memprediksi AKI telah diteliti secara intens pada beberapa kondisi klinis. Dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang, penting untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut berguna dalam mengkonfirmasi diagnosis AKI pada pasien yang sudah mengalami AKI, atau sebagai prediktor awal pada pasien yang sedang mengalami AKI. Hal tersebut merupakan dua entitas yang memiliki dampak klinis yang berbeda. Dalam aplikasi klinis penanda biokimiawi, penanda tersebut harus mampu membuktikan dapat lebih akurat dibandingkan baku emas pemeriksaan dengan menggunakan kreatinin serum (Hilde et al, 2012). Terdapat empat kategori utama dari penanda biokimiawi AKI yang beberapa banyak diteliti sebagai penanda diagnosis awal dari AKI (tabel 2.3). 23 Tabel 2.3. Penanda Biokimiawi AKI(Hilde et al., 2012) Tipe Penanda Biokimiawi Penanda fungsional Protein upregulated Protein dengan berat molekul rendah Enzim Penanda Biokimiawi Kreatinin serum dan plasma, Cystatin-C serum NGAL, KIM-1, L-FABP dan IL-18 Cystatin-C urine NAG, α-GST, π-GST dan AP Cystatin-C, cystatin-C; NGAL, neutrofilin gelatinase associated lipocalin; KIM-1, kidney injury molecule-1; L-FABP, Liver fatty acid binding protein; α-GST,Alpha-glutathiones-transferase; π-GST, pi-glutathiones-transferase; AP, alkaline phosphatase Kreatinin serum merupakan hasil degradasi dari sel otot dan mencerminkan kemampuan glomerulus untuk melakukan filtrasi yang efisien. Kreatinin serum memiliki akurasi prediksi yang buruk terhadap kejadian cedera ginjal, terutama pada kejadian awal AKI. Pada kasus penyakit kritis, konsentrasi kreatinin serum sangatlah berfluktuatif sebagai akibat dari status volume pasien yang dilutif, efek katabolisme penyakit kritis, dan peningkatan ekskresi tubular yang disertai dengan penurunan fungsi ginjal. Lebih jauh, setelah kejadian cedera ginjal, peningkatan kreatinin serum berlangsung lambat (Hilde et al, 2012). 2.4.2. Penanda Biokimiawi AKI Baru: Fokus pada Cystatin-C Cystatin-C merupakan inhibitor protease cysteine non-glikosilasi yang berukuran 13 kDa yang diproduksi oleh seluruh sel berinti dengan laju yang konstan. Pada subyek yang sehat, Cystatin-C plasma diekskresikan melalui filtrasi glomerular dan dimetabolisme secara sempurna oleh tubulus proksimal. Beberapa penelitian menyimpulkan superioritas Cystatin-C plasma terhadap kreatinin serum untuk mendeteksi penurunan kecil dari laju filtrasi glomerulus. Interpretasi kadar Cystatin-C plasma biasanya memiliki bias pada pasien dengan usia tua, perbedaan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, kebiasaan merokok dan tingginya kadar C-reactive protein (CRP). Dan Kadar Cystatin-C akan dipengaruhi oleh fungsi tiroid abnormal, penggunaan obat-obatan imunosupresan dan keganasan (Nejat et al, 2010). Beberapa studi mengenai Cystatin-C mendemonstrasikan akurasi yang sangat baik dalam diagnosis awal terjadinya AKI pada 24 hingga 48 jam sebelum ditegakkan diagnosis AKI (Tabel 2.4) (Ferna´ndez et al, 2011). Sedangkan apabila dibandingkan penanda biokimiawi lainnya NGAL memiliki spesifisitas yang baik, namun sensitivitas untuk diagnosis awal AKI tidak terlalu baik. NGAL merupakan protein berukuran kecil yang melekat pada neutrophil gelatinase pada granula 24 spesifik leukosit. Pada ginjal normal, ekspresi NGAL hanya ditemukan pada tubulus distal dan ductus kolektivus, sedangkan pada kejadian AKI, protein ini juga dapat ditemukan pada tubulus proksimal dan filtrat glomerulus (Nejat et al, 2010). Tabel 2.4. Penelitian Penanda Biokimiawi Diagnosis Awal AKI (Ferna´ndez et al, 2011). Fernandez dan kawan-kawan (Ferna´ndez et al, 2011), juga telah membuktikan bahwa Cystatin-C lebih superior dibanding pengukuran standar fungsi ginjal dalam memprediksi resiko kematian dan hospitalisasi akibat gagal jantung pada pasien dengan ADHF. Sedangkan sebuah penelitian berbasis populasi ruang rawat intensive menyimpulkan bahwa Cystatin-C lebih superior dibandingkan dengan kreatinin plasma dalam menilai perburukan fungsi ginjal lebih awal. Namun, keberadaan pemeriksaan Cystatin-C maupun beberapa penanda biokimiawi AKI (selain kreatinin serum) dirasa masih menjadi kendala dalam penerapan di praktik klinis sehari-hari (Nejat et al, 2010). 25 2.5. Penelitian Yang Relevan Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa AKI merupakan diagnosis tersering dalam melakukan konsultasi dengan bagian nefrologi, yang mengandung peningkatan risiko mortalitas dan morbiditas dalam praktik klinik sehari-hari. Namun, disamping peningkatan insidensi AKI dalam beberapa tahun belakangan, para dokter tidak memiliki banyak alat diagnostik klinis untuk menentukakn kemungkinan progrsifitas AKI. Peningkatan stratifikasi risiko pada pasien akan sangat krusial dalalm menentukan langkah terapi yang bertujuan melakukan penatalaksanaan AKI secara awal. Sebagai tambahan dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi ledakan penelitian dalam mencari penanda biokimiawi baru untuk melakukan diagnosis dini AKI, beberapa penanda tersebut telah menunjukkan kemampuan yang beragam dalam memprediksi progresifitas AKI (Koyner et al, 2015). Namun, walaupun investigasi terhadap penanda-penanda biokimiawi sangat intens dilakukan, utilitas dari penanda tersebut tetap belum menjadi dasar penegakan diagnosis, dan sebagian besar klinisi tidak memiliki akses terhadap pemeriksaan tersebut. Koyner dan kawan-kawan telah menunjukkan bahwa produksi urin dalam 2 jam setelah dilakukan uji beban furosemide/ furosemide stress test (FST) dosis tinggi (1mg/kg berat badan bagi pasien naif, dan 1.5mg/kg berat badan bagi pasien yang telah terpajan furosemide sebelumnya) pada pasien dengan AKI awal, memiliki nilai prediksi untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami perburukan. Area dibawah kurva ROC (receiver operating characteristic) pada produksi urin 2 jam setelah FST digunakan untuk memprediksi progresifitas menuju AKI tahap 3 dengan nilai 0.8760 dan p=0.001. Titik potong ideal dalam memprediksi progresifitas AKI selama 2 jam pertama adalah dengan produksi urin <200ml (100ml/ jam) dengan sensitivitas 87.1% dan spesifisitas 84.1% (Chawla et al, 2013). 26 2.6. Kerangka Pikir Gagal jantung akut curah jantung metabolisme aerobik ATP PCWP hipoksia tekanan vena sentral aktivitas apparatus juxta glomerolus aktivitas pompa Na2+/K+ ATP-ase gradient filtrasi ginjal renin Retensi Na2+ intrasel Angiotensin II Edema sel vasokonstriksi onkosis GFR AKI kreatinin serum cystatin-C plasma overhidrasi Furosemide stress test produksi urine 2 jam > 200 cc Gambar 2.6 Kerangka pikir penelitian Keterangan : merangsang/ memicu : menghambat : meningkatkan : menurunkan : variabel-variabel yang diteliti 2.7 Hipotesis Furosemide stress test dapat digunakan sebagai penanda diagnosis AKI pada pasien dengan gagal jantung akut.