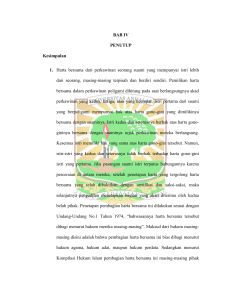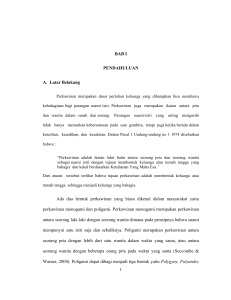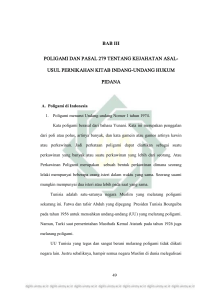BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Poligami menjadi isu kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga terjadi di umat agama lain yang tersebar di berbagai belahan dunia 1. Legalitas praktik poligami di negara-negara Barat tidak diakui dan bahkan dilarang, tetapi realitasnya bukan berarti tidak ada praktik poligami. Sementara, perkawinan monogami menjadi tuntutan legal negara Barat, tetapi banyak yang mempraktikkan hubungan intim di luar nikah (mistress) di tempat-tempat yang berbeda, atau dengan model gundik atau disebut de-facto poligamy (Nurmila, 2009). Hal ini dipraktikkan oleh ethnis tertentu dan komunitas keagaamaan tertentu pula2. Seperti halnya, praktik poligami di persoalkan di Barat, khususnya oleh pemerintah British Columbia pada Januari 2009 yang muncul di berbagai media, terkait praktik poligami dua tokoh komunitas keagamaan, Winston Blackmore dan James Oler. Akhirnya pada Oktober 2009 pemerintah Columbia melarang praktik poligami melalui konstitusi code kriminal pasal 29; sebab bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender (Quebec, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, isu poligami dalam dunia Islam kontemporer selalu didasarkan pada hak-hak perempuan, seperti Undang-Undang tentang Personal Status tahun 1957 di Tunisia, Undang-Undang Personal Status tahun 1 Poligami dipraktikkan lebih dari 850 kelompok –kelompok masyarakat, sebagian besar berkembang di kawasan Sahara Afrika, Mesir, dan Asia. Jumlah 20-50% semua perempuan hidup dalam poligami dalam beberapa budaya. Lihat Journal of Global Social Work Praktice, Volume 3, Number 1, May/June 2010. File:///E:/poligamy/...htm. 2 Introduction to Sociology/family-wikibooks, open books for an op…file://E:/poligamy%20in%20Sociology%20 perspectives.html. Diakses 31/10/2013. 1 2 1959 di Irak, the Polygamy Act 1958 di Moroco, Marriage and Divorce Act 1965, the Laws of Cyprus di Turkey. Seperti praktik poligami masyarakat Iran harus mendapat persetujuan tertulis dari peradilan Qadhi, di Tunisia poligami secara tegas dilarang, sedangkan di Irak menikah lebih dari satu perempuan diijinkan hanya dengan ijin peradilan (Mohammad, 2012). Sejumlah negara-negara Islam ini memiliki ketentuan legal berbeda yang berhubungan dengan praktik poligami. Kebolehan poligami ini merujuk berbagai mazhab fikih dan ahli tafsir sebagaimana diungkapkan oleh Azzuhaili (1989) dan Ashabuni (1980). Kebolehan berpoligami menjadi argumen atau legitimasi baik dalam konteks individual maupun oleh Negara yang berpegang pada hukum Islam. Menurut Abu Zayd (2003) kebolehan berpoligami dalam hukum Islam, secara historis hanya untuk mengatasi problem yang muncul di masyarakat, yaitu ketika umat Islam banyak yang wafat pada perang Uhud dan saat itu banyak janda dan anak yatim yang terlantar. Meskipun demikian, praktik poligami tersebut merupakan tradisi yang ada sebelum Islam yang tak terbatas dalam bilangan isterinya tetapi dibatasi oleh Islam hanya sampai empat isteri dengan persyaratan perlakuan adil. Teks al-Qur’an menegaskan bahwa perlakuan adil tidak akan mampu diwujudkan oleh mereka yang berpoligami. Secara faktual, praktik poligami yang berkembang saat ini tidak mendasarkan pada argumen sosio-historis ketika poligami mendapat legitimasi oleh Nabi Muhammad saw untuk memecahkan ”kelangsungan dan perlindungan para janda dan anak yatim” (Wadud, 1999). Bahkan yang berkembang, adalah pemahaman atau interpretasi hukum Islam (fiqh) yang keluar dari konteks 3 kesetaraan dan menanamkan kembali dominasi laki-laki dan menumbangkan eksistensi perempuan (Abu Zayd, 2003). Isu poligami dalam masyarakat muslim Indonesia juga tidak kalah kontroversial, dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan, baik kalangan kelas sosial tinggi maupun kalangan menengah ke bawah dengan berbagai latar belakang dan argumentasi yang berbeda-beda. Aktor poligami ada yang memiliki modal ekonomi yang kuat, modal sosial, dan bahkan kalangan agamawan ataupun para tokoh agama (Nurmila, 2009). Secara faktual, poligami berimplikasi kepada kaum perempuan mengalami subordinasi, dan berefek negatif pada perkembangan kepribadian anak. Eksistensi perempuan menjadi subordinat disebabkan oleh struktur sosial yang diorganisasi oleh kaum laki-laki melalui institusi rumah tangga, misalnya terjadi kecemburuan baik di antara kedua istri ataupun anak-anaknya. Ketegangan ini akan memunculkan ketegangan-ketegangan mental dan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, persaingan, dan sabotase dalam keluarga (Panos, 2010). Ketegangan ini berimplikasi pada relasi yang saling menindas sebagaimana disebut oleh Collins (2001) intersectionality, yaitu bekerjanya relasi-relasi gender dan kelas sosial bertemu pada satu titik potong dan berimplikasi pada berlangsungnya praktik dominasi dan subordinasi dalam waktu simultan. Situasi ini berlangsung dalam waktu yang panjang memenjarakan kaum perempuan, dan bahkan sudah menjadi kesadaran dan aturan melalui legalitas keagamaan dan budaya masyarakat. Selain perempuan tersubordinat oleh struktur sosial, dimensi interaksi sosial juga memproduksi perempuan pada situasi subordinat, misalnya 4 adat kesopanan yang membatasi ruang aktifitas perempuan; perempuan selalu dikendalikan oleh penilaian ketidakwajaran, sehingga perempuan tidak bebas bertindak untuk menentukan opsi-opsi yang dimilikinya. Di samping kedua dimensi struktur sosial dan interaksi sosial, dimensi ideologi dan institusi negara melalui aturan-aturan atau regulasi formal yang mengikat dan tidak setara yang mengakibatkan posisi perempuan dalam situasi subordinat. Situasi ini, menurut Collins (2000) adanya manipulasi ideologi, budaya, dan domain hegemoni yang bekerja sebagai suatu pertautan di antara institusi-institusi sosial, praktik-praktik organisasi dan interaksi sosial yang terjadi pada level kehidupan sosial atau yang dinamakan dengan konstruksi matrix of domination. Persoalan dimensi kekuasaan dalam relasi laki-laki dan perempuan khususnya perbedaan pemaknaan poligami menjadi bagian yang terpenting sebagai wacana dan praktik sosial, karena kompleksitasnya yang tidak lepas dari kondisi sosio-kulturalnya. Wacana poligami merupakan praktik sosial yang tidak lepas dengan pengetahuan poligami itu sendiri dan relasi kekuasaan yang berkembang di dunia sosial. Masyarakat dapat tunduk dan dikendalikan tidak hanya dengan secara langsung, tetapi dapat juga melalui wacana dalam bentuk aturan, undang-undang, berbagai karya, atau bentuk-bentuk lainnya. Sarana untuk merealisasikan upaya tersebut, oleh Hammer dan Killner (2009) disebut sebagai agen sosialisasi ideologi. Dalam konteks tersebut, hasil karya sastra merupakan modal symbolic power atau kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991) Kekuasaan dalam pengertian tersebut melahirkan intersectionality, terlihat melalui gagasangagasannya sebagai sarana pertarungan dalam ruang sosial. Dengan menggunakan 5 ragam identitas gender dan kelas yang diproduksi melalui keyakinan agama, seksualitas, struktur patriarki, kebangsaan dan struktur sosial lainnya menjadi basis dalam membangun wacana poligami. Sedangkan kelas sosial meliputi kewarganegaraan asing dan pribumi, kekuatan modal ekonomi, sosial dan budaya bekerja memproduksi ketimpangan dalam bentuk ”dominasi” dan ”subordinasi”. Dalam konteks ini, upaya untuk menganalisis representasi intersectionality relasi kuasa yang dibangun oleh pengarang Ayat-Ayat Cinta menjadi penting dalam konteks yang lebih luas, dengan cara pengungkapan pemaknaan yang melampaui realitas teks wacana novel tersebut. Daya imajinatif dan kreativitas pengarang menjadi penting untuk berperan dalam konstruksi wacana (Ratna, 2007). Berkaitan dengan gagasan yang disampaikan kepada para pembaca atau masyarakat luas, karya sastra memiliki posisi yang strategis berupa agenda melalui imajinasi para pengarang yang berhubungan dengan masyarakat sekitar (Disher, 2001). Tentunya agenda antara pengarang karya sastra berbeda satu sama lain, tergantung pada konteks realitas yang ada (Nurgiyantoro, 2009). Selain memiliki posisi strategis kepada para pembaca, karya sastra berperan sebagai transformasi gagasan pengarang (Ratna, 2009; Adi, 2011) pengarang merupakan wakil masyarakat, sebagai konstruksi transindividual, bukan dirinya sendiri, serta terkondisikan secara sosial, atau dipengaruhi oleh persoalan masyarakat sebagai sumber gagasannya. Novel merupakan salah satu jenis karya yang dibangun dari relasi pengarang dan lingkungan sosial sebagai sarana/instrumen pertarungan di ruang sosial. 6 Habiburrahman El Shirazy salah satu sastrawan Indonesia menawarkan gagasan romantika novelnya, Ayat-Ayat Cinta dengan wacana poligami. Ayat-Ayat Cinta merupakan modal simbolik dan sekaligus berpengaruh pada capaian-capaian modal lain yang menjadi agenda atau kepentingan pengarangnya. Novel Ayat-Ayat Cinta secara sosiologis telah menancapkan dirinya sebagai novel paling laris dan luar biasa fenomenal3, dalam perjalanan sastra Indonesia, baru kali ini dapat meraup penjualan fantastis, bahkan memunculkan wacana sastra Islam. Problem rivalitas dari dua gelombang sastra yaitu kejenuhan isu seksualitas dan moralitas justru terjadi pada tataran horison harapan pembaca Ayat-Ayat Cinta yang dilatarbelakangi oleh hasrat melakukan pertarungan pada tema-tema yang dianggap berseberangan. Pertarungan yang sekian lama tak terucapkan tiba-tiba seperti memperoleh saluran selepas Ayat-Ayat Cinta membawa gelombang kehebohan. Kemudian muncul kesadaran untuk menciptakan label sebagai penanda identitas (Mahayana, 1998, 2011). Dengan demikian, label sastra Islam yang dilekatkan pada novel Ayat-Ayat Cinta sebagai salah satu ikonnya, sebenarnya sekadar klaim untuk menunjukkan panji identitas. Dalam konteks pertarungan tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu Pertama, strategi dan perjuangan pengarang melalui karyanya, untuk mendapatkan agenda yang diinginkan. Di satu sisi, diskursus poligami menjadi problematis ketika berhadapan masyarakat muslim sendiri dan dunia Barat. Di sisi lain, isu yang mengartikulasikan kebebasan seks sebagai bentuk trend novelis kaum perempuan. Kedua, novel Ayat-Ayat Cinta hadir dalam momentum yang berbeda 3 Novel Ayat-Ayat Cinta terjual lebih dari 400.000 eksemplar, dan filemnya memikat hingga 3 juta penonton. http://groups.yahoo.com/oyr79/message/2365. Diakses 28 Maret 2013. 7 dan menjadi pertarungan ideologis terhadap isu seksualitas novel-novel sebelumnya, seperti novel karya Ayu Utami, yaitu Saman (1998), novel ini memberi pesan tidak sekadar menabrak bahkan menghancurkan pandangan masyarakat tentang konsep virginitas atau kesucian seksualitas, hubungan pranikah, perselingkuhan, dan perkawinan. Djenar Maesa Ayu dengan karyanya Jangan Main-Main dengan Kelaminmu (2004). Atau dengan kata lain Ayat-Ayat Cinta Hadir dengan ideologi yang berbeda dengan novel era 2000-an. Ketiga, memposisikan gagasan kebolehan poligami dalam perspektif yang berbeda dengan arus utama umat Islam. Kepentingan poligami dikaji dalam formulasi darurat dan bersifat makro. Berangkat dari ilustrasi di atas, novel Ayat-Ayat Cinta menjadi penting untuk dikaji sebagai produk budaya yang menjadi sarana ideologis dalam pertarungan di arena sosial dari latar belakang pengarang yang berbeda satu sama lainnya. Dalam konteks ini, representasi kuasa dalam wacana poligami menjadi entry point yang dapat ditelusuri untuk mengungkap relasi kekuasaan yang muncul di tengah-tengah permainan pemaknaan konsep ganda yang dipertentangkannya dalam memproduksi dan mereproduksi dominasi ideologinya. Representasi ini pertama kali dapat dilacak pada jaringan ideologi yang didasarkan pemikiran/mazhab dalam hukum Islam menjadi tahap penting untuk membaca keterwakilan kelompok ideologis, baik yang dominan maupun yang subordinat, dalam konteks sosio-historis. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menelusuri wacana lain yang kemungkinan berperan memproduksi kompleksitas 8 poligami dalam konteks Indonesia, secara langsung ataupun tidak, merupakan perwujudan ideologi-ideologi yang sedang bertarung. 1.2 Rumusan Masalah Berangkat dari konteks kehidupan masyarakat, bahwa maksud dan tujuan poligami seakan dilegalkan, tetapi sesungguhnya ada kontestasi-kontestasi terkait dengan persimpangan kelas sosial dan gender. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan beberapa hal, sebagai berikut: a. Bagaimana representasi relasi-relasi intersectionality kelas sosial dan gender dalam konteks poligami melalui novel Ayat-Ayat Cinta? b. Kontestasi-kontestasi apa saja yang muncul di seputar persoalan poligami ? c. Dalam konteks apa poligami didukung? Bagaimanakah interelasi sosiokultural dan politik yang berpengaruh pada diskursus poligami novel Ayat-Ayat Cinta? 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karya sastra tentang relasi persimpangan atau intersectionality kelas sosial dan gender dalam diskursus poligami di ruang sosial. Pentingnya tujuan penelitian ini didasarkan pada argumen, bahwa realitas kehidupan sosial, perempuan sering diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Situasi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu panjang terkungkung oleh nilai-nilai patriarki dan bias gender, baik dalam memandang relasi kuasa dan kelas sosial antar laki-laki dan perempuan. Situasi ini 9 menempatkan perempuan selalu dirugikan dan ataupun subordinat. Relasi kuasa keduanya, memproduksi dominasi laki-laki melalui berbagai institusi sosial, peran negara dan berbagai birokrasi dalam bentuk perundang-undangan baik pada domain publik maupun domestik, ideologi, budaya, kesadaran, dan hubungan interpersonal dalam interaksi sosialnya (Collins, 2000). Beberapa dimensi tersebut bekerja dalam konteks poligami, baik dalam dataran wacana maupun praktik sosial. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi wacana kritis yang tujuan pokoknya adalah merumuskan dan mensistematisasikan suatu gagasan menjadi konsep utuh sebagai ikhtiar pencarian ideologi tertentu yang ditawarkan oleh pengarang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan menganalisis representasi dominasi dan subordinasi relasi kelas sosial dan gender, serta memiliki efek multiplikatif sebagai suatu proses sosial atau sebagai suatu persimpangan yang lain. Melalui pengungkapan tersebut akan diperoleh pemahaman tentang implikasi dari relasi antar kelas sosial dan gender dalam kompleksitas poligami. b. Untuk mengetahui dan menganalisis ideologi-ideologi yang terlibat dalam pertarungan di seputar wacana poligami. Melalui pengungkapan tersebut akan diperoleh pemahaman ideologi dominan yang dibangun oleh pengarang novel Ayat-Ayat. c. Untuk mengetahui dan menganalisis wacana-wacana lain yang ikut berpengaruh munculnya wacana poligami novel Ayat-Ayat sosiokultural dan politik Indonesia. Cinta dalam konteks 10 1.4 Keaslian Penelitian Penulis belum menemukan penelitian khusus tentang relasi-relasi persimpangan (intersectionality) kelas sosial dan gender dalam poligami yang objek kajiannya adalah peran novel dalam konteks sosial. Penelitian lain yang pernah dilakukan antara lain: Jackson (2008) melakukan penelitian tentang The Intersection of Race and Gender in “Down These Mean streets” karya Piri Thomas. Subjek yang diteliti tentang diskriminasi perempuan dalam wilayah domestik atau keadilan di rumah tangga, marjinalisasi dalam ranah sosial, pelabelan negatif, inferioritas perempuan kulit hitam, bahkan laki-laki kulit hitam, hierarki sosial yang menempatkan perempuan laki-laki kulit hitam pada level yang sama dalam situasi tersubordinasi dengan proses rasialisasi kulit putih, laki-laki sebagai agen kekerasan domestik dan sosial terhadap perempuan. Perbedaan dengan penelitian ini, adalah Johanna Jackson menekankan representasi politik seksual, gagasan pemikiran maskulinitas dan wacana laki-laki berkarakter aktif tetapi perempuan dalam kehidupannya menerima peran-peran pasif, sedangkan penelitian ini menempatkan peran karya sastra sebagai modal simbolik dengan relasi-relasi intersectionality kelas sosial dan gender menggunakan diskursus poligami dalam kehidupan masyarakat. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Nasution (1996) dan telah diterbitkan dengan judul Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh. Penelitian ini dilakukan dengan pemetaan pendapat ahli fiqh yang dikategorisasikan dalam tiga pendapat. Pertama, ketidakbolehan melakukan poligami, kecuali dalam kondisi tertentu atau darurat. Poligami hanya mungkin 11 dapat dilakukan suami dengan syarat-syarat tertentu, misalnya ketidakmampuan isteri untuk mengandung atau melahirkan, tuntutan jaman, berbuat adil dalam hal akomodasi dan tuntutan batin isteri. Kedua, kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat. Beristeri lebih dari empat bertentangan dengan kasus seorang shahabat yang dibolehkan wali maksimal empat, fakta sejarah mulanya Nabi Muhammad saw monogami sampai 25 tahun lamanya, sedangkan praktik poligami Nabi ketika berumur 50 tahun dan isterinya para janda yang memiliki anak yatim dan hanya Aisyah yang masih perawan (berumur enam tahun). Ketiga, menikahi perempuan lebih dari empat diperbolehkan. Penafsiran ayat Al-Nisa’/4:3 dipahami dalam bentuk penambahan menjadi sembilan dan didukung oleh perbuatan Nabi pernah mempunyai isteri sembilan dalam waktu yang bersamaan. Perbedaannya adalah penelitian Nasution lebih memperhatikan praktik poligami dari segi persyaratan material dan non material, sedangkan penelitian ini menekankan pada relasi-relasi kekuasaan dalam praktik poligami dalam konteks sosio-kultural dan politik. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nurmila (2009) disertasi yang diterbitkan tentang Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia. Meneliti latar belakang sejarah dan politik Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan hubungannya dengan regulasi pemerintah seperti PP 10 dan Kompilasi Hukum Islam. Penyelidikan tentang kompleksitas dunia hukum Islam dan interpretasinya para Ulama (Muslim Scholars), Pemuka agama, masyarakat yang mempraktikkan poligami dan para lawyer. Salah satu hasilnya, adalah praktik poligami tidak memperhatikan berbagai kepentingan perempuan 12 dan hanya didasarkan pada kepentingan satu pihak dan bahkan praktik poligami secara sembunyi-sembunyi (illegal). Perbedaannya adalah penelitian Nurmila menekankan pada dampak poligami terhadap keutuhan keluarga dan kepentingan laki-laki tanpa memperhatikan pemahaman konsep keadilan bagi perempuan, sedangkan penelitian ini menekankan gagasan representasi politik perempuan atas kekuatan modal yang dimilikinya dalam pemaknaan poligami, dan bahkan kepentingan-kepentingan perempuan dilihat dalam relasi intersubyektif atas dominasi kekuasaan. 1.5 Manfaat Penelitian a. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kritik atas praktik poligami yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Poligami merupakan praktik sosial tidak hanya didasarkan pada kepentingan individual, tetapi harus didasarkan pada argumentasi yang bersifat makro. Sehingga diharapkan terbangun kesadaran untuk melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan, khususnya ajaran yang berbicara tentang relasi gender dan kelas sosial dalam poligami. b. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam hal penerapan atas kajian interseksionalitas berdasar anggapan, bahwa tidak ada perempuan atau laki-laki yang generik, artinya keduanya memiliki keistimewaan, dan kelemahan tertentu dalam relasi sosialnya. Dalam relasi sosial, baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak tertindas secara berlapis yang disebabkan oleh struktur sosial, relasi interpersonal, dan perudang-undangan terutama dalam kompleksitas praktik poligami. 13 c. Penerapan analisis wacana kritis dalam penelitian ini, bermanfaat dalam memahami kontestasi-kontestasi intersektionalitas relasi gender dan kelas sosial, serta interelasi sosiokultural dan politis di seputar praktik poligami. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan untuk melakukan penelitian lanjutan, khususnya bagi peneliti budaya dan media yang berminat mengkaji dari aspek lain. 1.6 Tinjauan Pustaka Objek penelitian ini adalah menempatkan peran novel sebagai sarana pertarungan di ruang sosial dengan diskursus poligami. Oleh karena itu, karyakarya yang pernah dikaji oleh banyak kalangan tentang relasi laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim (2010) dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Conservative Islam Turn or Popular? An Analysis of Film Ayat-Ayat Cinta. Di dalam penelitiannya diungkapkan bahwa filem Ayat-Ayat Cinta lebih dominan corak pemikiran Islam fundamentalis dan modernis yang mendukung poligami, namun persoalan pernikahan antar agama lebih bercorak pada Islam liberal. Prima Gusti Yanti (2010) dari Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dengan judul disertasi, Representasi Ras, Kelompok Etnik, Kelas Sosial, dan Gender Studi Pascakolonialisme dalam Novel-novel Remy Sylado. Di dalam penelitiannya diungkapkan perbedaan representasi ras, kelompok etnik, kelompok sosial, dan gender pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tetap 14 berlangsung meskipun dalam bentuk yang berbeda. Representasi perempuan dalam novel masa penjajahan mengalami penindasan ganda, perempuan tidak berpendidikan mengalami penindasan, sedangkan perempuan bangsawan mendapat tempat yang lebih tinggi. Pada masa pasca kemerdekaan perempuan mampu mengaktualisasikan diri dan berprestasi dalam berkarier. Penelitian yang dilakukan oleh Nazla Maharani Umaya (2006) dengan judul Fenomenologi Eksistensial Seorang Nyai pada Novel Nyai Dasima versi G. Francis dengan Kajian Fenomenologi Hussrel. Begitu pula Novel Nyai Dasima versi Rahmat Ali, dikaji oleh Sugihastuti dan Isna Hadi Saptiawan (2007) tentang "Gender dan Inferioritas Perempuan" dengan menggunakan kritik sastra feminis. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketertindasan yang dialami perempuan. Demikian halnya, citra inferior yang disandang perempuan dalam novel tersebut menyiratkan tertindasnya perempuan secara mental, yang muncul sebagai bentuk kekalahan perempuan dalam hubungannya dengan dunia patriarki. Tulisan Muhamad Adji dalam Jurnal Yin Yang STAIN Purwokerto (2010) tentang "Peran Perempuan Indonesia dalam Perjuangan Kebangsaan (Membaca Tokoh Nyai Ontosoroh pada Novel Bumi Manusia). Kajian ini mengungkapkan tentang tokoh perempuan Nyai Ontosoroh sebagai seorang pribumi yang menjadi gundik (isteri tidak sah oleh orang Belanda), dan ia sebagai representasi pribumi kelas menengah ke bawah yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, sosial, dan hukum yang berkembang menjadi persoalan rasisme dan juga menjadi representasi inferioritas perempuan terhadap struktur patriarki. 15 Berdasar penelusuran penulis, untuk sementara belum ditemukan penelitian lain yang menempatkan peran novel dalam relasi-relasi intersectionality kelas sosial dan gender dalam diskursus poligami serta penelitian yang menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu tentang relasi dialektika agen dan struktur masyarakat. Kepentingannya adalah untuk menganalisis tindakantindakan agen dan formasi diskursif dan relasi sosial. Oleh karena itu, kajian relasi-relasi persimpangan gender, kelas sosial melalui diskursus poligami dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy, akan memberikan kontribusi baru dalam kajian budaya dan media. 1.7 Kerangka Teori Acuan teoritis di bawah ini menjadi frame of work penelitian tentang persimpangan (intersectionality) kelas sosial, gender dalam poligami. Acuan teoritis ini dibangun berdasarkan konsep atau teori dari berbagai pendapat para ahli yang kemudian dikonfirmasikan ditingkat empirik, yaitu teks novel sebagai sebuah karya yang merupakan modal simbolik dan digunakan sebagai sarana dalam pertarungan wacana di ruang sosial. Pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi baru dalam bidang kultural dan media. Adapun konsepkonsep teoritik penelitian ini, mencakup kajian tentang budaya, teori Intersectionality, dialektika Agency dan strukturasi Bourdieu, konsep gender, kelas sosial dan poligami, sebagai berikut: 16 a. Budaya merupakan Sarana Praktik Sosial Penggunaan term ”budaya atau culture” merupakan istilah yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, bahkan cenderung bertambah luas dan beragam (Ratna, 2007). Kompleksitas istilah tersebut tidak merepresentasikan suatu entitas dunia objek yang berdiri-sendiri, tetapi pada pemahaman penanda yang selalu berubah-rubah. Akibatnya pemahaman sangat tergantung pada kepentingan yang berbeda pula (Barker, 2004). Terkait dengan karya sastra atau karya seni pada umumnya, kajian budaya berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman antara fiksi dan fakta. Dengan demikian keseluruhan gejala seni dan kehidupan, sebagai tanda, mempunyai acuan pengetahuan kultural (Disher, 2001). Subjek bukan member of resources atau sumber pengetahuan, tetapi wacana yang memposisikannnya, baik wacana lisan maupun tulisan sebagai praktik sosial (Piliang, 2003; Ratna 2007). Konsep ini tidak jauh berbeda dengan formulasi Bourdieu (1990), tentang keterkaitan praktik sosial dengan habitus dan modalitas dalam arena sosial. Berarti wacana sekaligus membentuk objek dan subjek. Praktik sosial dalam bingkai teoritik konsep budaya tersebut di atas, memberikan pemahaman, bahwa poligami merupakan salah satu objek penerapan dalam lingkup kultural. Berangkat, dari pemahaman praktik sosial di atas, bahwa salah satu konsep kultural kontemporer menekankan persimpangan kekuasaan (intersection of power) dan pemaknaan dengan suatu pandangan untuk mempromosikan perubahan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia (Barker, 2004). Senada dengan itu, beberapa ilmuwan memberikan definisi budaya atau kultur 17 beragam sesuai dengan kepentingannya. Raymond Williams, misalnya, memberikan lingkup batasan budaya menjadi tiga hal. Pertama, budaya dimaknai sebagai proses general dari proses pengembangan intelektual, spiritual, dan estetika. Alasan ini didasarkan pada observasinya kondisi perkembangan budaya Eropa, seperti munculnya tokoh-tokoh besar yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Kedua, budaya dimaknai sebagai way of life, yang berkaitan dengan individu atau kelompok pada waktu atau jaman tertentu, misal pemaknaan suatu upacara keagamaan kelompok tertentu. Ketiga, budaya diartikan dengan bentuk karya dan praktik dari aktivitas intelektual, khususnya artistik (Storey, 1993). Berdasarkan pemaknaan budaya yang ketiga inilah, sebagai proses elaborasi intelektualitas, berupa karya novel yang mewacanakan poligami merupakan bentuk praktik sosial dan intelektual menjadi penting untuk dikaji dengan pendekatan teori budaya. Gans (1974) memandang budaya lebih pada penekanan pada eksistensi produk-produk budaya yang tidak jauh dari kehidupan masyarakat, sebagai pencipta dan konsumer, serta yang memaknainya. Lebih jauh Durham dan Kellner (2006) menjelaskan pengertian budaya yang tidak jauh berbeda, yaitu masyarakat dewasa ini membentuk serangkaian wacana, cerita-cerita/stories, image, tayangan-tayangan spectakuler, bentuk-bentuk budaya dan praktik-praktik sosial yang mengeneralisasikan pemaknaan, identitas, dan efek-efek politis. Oleh karena itu, Storey (2007: 4) menganggap, bahwa budaya bersifat politis dalam pengertian yang sangat spesifik, yaitu sebagai ranah pergumulan dan konflik. Artinya adanya proses pertarungan ideologis dengan menghadirkan makna ganda, makna selalu 18 merupakan akibat dari tindakan artikulasi, sebab makna harus diekspresikan dalam konteks yang spesifik. Sejalan dengan beberapa pengertian budaya ini, novel merupakan salah satu produk budaya yang tidak lepas dari pemaknaan-pemaknaan ideologis terkait dengan wacananya. Perbedaan definisi di atas, memberikan pemahaman tentang kompleksitas budaya, dan melahirkan kontestasi pemaknaan berbeda, tergantung pada tujuan dan subjek yang memaknainya. Dalam konteks itulah, istilah budaya cenderung dipahami sebagai ranah pergumulan konflik yang bersifat politis dan ideologis, serta bermain di dalam konstelasi kekuasaan seperti halnya pendapat Barker (2000) dan Storey (2007) bahwa budaya adalah bersifat politis sebab menjelaskan ekspresi dari relasi-relasi kekuasaan kelas sosial yang menaturalisasi tatanan sosial sebagai fakta yang berhubungan dan adanya upaya pengaburan relasi-relasi dominasi sehingga bersifat ideologis. Benang merah yang menghubungkan antara novel dan budaya tampak dari pandangan Williams maupun Gans. Keduanya menganggap budaya merupakan konsep yang membuka ruang pemahaman dengan sarat muatan ideologis dan politis. Oleh karena itu, novel sebagai produk budaya menjadi penting untuk dikaji dalam konsep budaya agar pemahaman peneliti didasarkan pada kerangka kerja pada konteks praktik diskursif ”poligami” dalam novel yang merupakan proses budaya yang potensial dengan sarat muatan isu politis dan ideologis. b. Intersectionality Kekuasaan: Ideologi Gender dan Kelas Sosial Salah satu konsep kultural kontemporer menekankan persimpangan kekuasaan (intersection of power) dan pemaknaan dengan suatu pandangan untuk 19 mempromosikan perubahan sosial dan memperbaiki kondisi kehidupan manusia (Barker, 2004). Dalam konsep intersectionality ini, banyak ahli dan teoritisi terlibat dalam upaya menafsirkan konsep tersebut. Crenshaw (1991) mengajukan konsep interseksional dengan model process-centered atau kerangka kerja analisis efek-efek interaksi dan multilevel, yaitu mengkaji efek-efek pokok yang berlapis tentang ketimpangan-ketimpangan, misalnya, kelas dan gender yang bertemu memiliki efek yang multiplikatif sebagai suatu proses sosial dan dapat dilihat sebagai suatu persimpangan yang lain. Pusat perhatiannya menekankan pada pemaknaan-pemaknaan kultural dan kategori-kategori konstruksi sosial atau analisis yang lebih bersifat interkategori, untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang lebih dinamis dari pada hanya penjelasan tentang satu kategori. Dalam memahami intersectionality tersebut, konsep itu dikembangkan lebih luas oleh McCall (2001), bahwa intersectionality tidak dilihat hanya satu level dalam satu aspek individual maupun satu organisasi. Intersectionality kelas dan gender bukan suatu jumlah lokasi-lokasi yang spesifik ditempati oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tetapi dipahami sebagai suatu proses melalui kelas sosial yang bekerja saling terjalin dengan pemaknaan-pemaknaan gender dan kelas yang multiplikatif. Proses tersebut tergantung dengan apa saja dan bagaimana kelas sosial dan gender dilihat sebagai sesuatu yang relevan karena seksualitas, otoritas politik, dan reproduksi atau yang lainnya. Berbeda dengan Prins (2006) menekankan strukturisasi sebagai proses sejarah bukan mulai dari struktur dan agency yang dihilangkan. Pernyataan Prins, tentang proses sejarah yang dapat dipahami sebagai proses dinamis dan aktif, 20 sebagaimana diperkuat oleh Walby (2007) gagasan intersectionality sebagai suatu ”sistem yang aktif” dengan efek-efek positif dan negatif, relasi-relasi non-linear, dan bukan hierarki yang overlap di antara beberapa organisasi yang ada. Artinya relasi-relasi bekerja secara dialektik antara satu dengan yang lain atau yang disebut dengan ”co-constructed”. Oleh Collins (2000) dijelaskan dalam bentuk matrixs of domination dan subordination, konsep ini menjelaskan kelompok atau individu yang memiliki komposisi social markers yang tepat akan masuk dalam kategori matrik dominasi, dan begitu sebaliknya. Intersectionality, dalam berbagai pengertiannya, merupakan instrumen untuk menjelaskan konstruksi relasi-relasi kekuasaan individu dan kelompok merupakan landasan teoritik yang penting untuk dipakai dalam membaca interaksi antar tokoh yang menampilkan praktik ideologis yang kemudian menempatkan novel sebagai media atau produk budaya. Munculnya berbagai kepentingan oleh berbagai individu dan kelompok dalam memaknai konsep poligami merupakan indikasi hadirnya ruang negosiasi dan kontestasi antar aktor dalam wacana utamanya. Pada konteks inilah, konsep intersectionality di atas membantu untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua dalam wacana poligami. Adapun beberapa dimensi kelas sosial, gender dan poligami dapat dikonsepsikan sebagai berikut: a) Konsep kelas sosial Istilah kelas sosial dapat didasarkan pada pengertian penguasaan materi di masyarakat dan pada waktu yang sama juga menguasai kekuatan intelektual 21 (Durham & Killner, 2006). Dengan kata lain, terjadi eksploitasi; penguasaan materi dan intelektual akan lebih mudah melakukan kontrol gagasan-gagasan produksi atau pada instrumen-instrumennya kepada pihak yang lemah, dan kesempatan hidup (life chances) atas akses sumber-sumber daya yang ada. Eksploitasi tersebut berpengaruh secara langsung atas kepemilikan material melalui jenis-jenis aset ekonomi masyarakat sebagai pertukaran di pasar (market exchanges). Hal ini diproduksi secara terus menerus oleh masyarakat kapitalis berupa transformasi teknis dan ekonomi (Wright, 2003). Oleh karena situasi ini secara empiris melahirkan konflik kepentingan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial, karena terjadi pola-pola institusionalisasi pengendalian yang timpang dan distribusi nilai guna barangbarang dan sumberdaya-sumberdaya yang ada di masyarakat, sebagai contoh dominasi penguasaan atas tanah, properti, uang, pekerjaan menjadi basis terjadinya ketimpangan kelas-kelas yang ada di masyarakat (Dill & Zambrana, 2009). Pendapat di atas, ketimpangan kelas sosial hanya dipahami dalam kerangka struktur ekonomi sebagai basis utamanya, namun tidak dipahami bagaimana ketimpangan kelas sosial dengan pendekatan konstruksi sosial masyarakat. Dalam hal ini, konsep kelas dapat dipahami sebagai relasi sosial yang tersusun dalam beberapa ranah, seperti ranah ekonomi, politik, dan ideologi yang masing-masing kemudian menjadi dimensi-dimensi kelas yang saling berhubungan (Bourdieu, 1984). Praktik dominasi dan subordinasi dalam ketiga ranah tersebut terjadi, ketika masing-masing aktor memiliki perbedaan modal yang dimilikinya. Dalam 22 konteks ini, bagi aktor sosial yang memiliki kekuatan modal ekonomi, politik, sosial dan budaya yang lebih tinggi akan menunjukkan perbedaan perilaku sosial dan konsepsi yang dimiliki masing-masing kelas (Bourdieu, 1977). Perbedaan perilaku atau gaya hidup, misalnya selera makan antara kelas atas dan kelas buruh akan berbeda. Biasanya perbedaan terletak pada orientasi pilihan makanan yang disajinya. Begitu pula sejauhmana dua kelas sosial yang berbeda dalam mengkonsepsikan pilihan makanan yang kaitannya dengan pemenuhan gizi bagi kebutuhan tubuhnya dan juga perbedaan tindakan lain aktor kelas tertentu. Perbedaan perilaku aktor kelas sosial dijelaskan oleh Bourdiue (1998) merupakan pilihan-pilihan berdasarkan sistem konsepsi yang bekerja dalam aspek kognisinya berimplikasi pada pilihan-pilihan sebagai perwujudan logika sosialnya. Perbedaan konsepsi dan perilaku sosial atau gaya hidup individu kelas sosial yang lebih tinggi atas modal yang dimilikinya sebagai wujud strategi kekuasaan. Sejauhmana individu-individu mempertahankan kekuasaan melalui perbedaan pilihan dalam tindakan-tindakannya untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Dengan demikian, perbedaan kelas sosial dapat dianalisis dalam kerangka kerja konsep habitus, modal dan ranah ekonomi, politik, dan doxa. b) Konsep Gender Perempuan dalam kehidupan sosial sering dinilai sebagai subjek ”Yang lain” atau sering dianggap menjadi ”konco wingking” dalam budaya Jawanya. Penilaian tersebut menjadi basis penentuan representasi sosial berkaitan dengan status dan perannya, karena keduanya untuk meneguhkan identitasnya sebagai subjek dalam 23 representasinya. Memposisikan perempuan pada ranah domestik dalam kehidupan sosial dan budaya di satu sisi sedangkan pada sisi yang lain, laki-laki diposisikan dalam ranah publik sering melahirkan ketegangan atau ketimpangan. Peneguhan identitas yang merujuk pada perbedaan peran dan status yang kemudian disebut gender, diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari konstruksi sosiokultural untuk membedakan identitas maskulin dan feminin atau sesuatu yang ditampilkan. Gender berbeda dengan jenis kelamin yang digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis (Kessler & McKenna, 1977). Konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat selalu dikaitan antara jenis kelamin yang berbeda, namun keduanya mengalami perubahan sebagaimana menurut Tierney (2010) berupa not fixed. Dikotomi konsep nature dan culture, contohnya, telah digunakan sebagai pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin. Sebagaimana pendapat Holmes (2009), sex merujuk secara fisik dan kromosom yang memproduksi jenis kelamin laki-laki atau perempuan seseorang. Sedangkan gender mendiskripsikan ekpektasi sosial, aturan-aturan dan norma-norma berhubungan dengan feminitas dan maskulinitas. Konstruksi sosial budaya yang berbeda atas relasi femimin dan maskulin berimplikasi pada ketegangan, ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Menurut Swatos (2010) bahwa ketimpangan gender didasarkan pada suatu situasi yang mana individu-individu dan kelompok memiliki pembagian yang tidak setara dalam hal distribusi kekuasaan, hak-hak yang harus didapatkan dan martabat atau 24 penghargaan yang lebih tinggi di satu pihak dan merendahkan pihak lain dalam kehidupan masyarakat. Perubahan konsep maskulin dan feminin ini disebabkan oleh adanya anggapan yang berbeda-beda di antara budaya masyarakat yang berbeda. Atau sesuai dengan konteks budaya setempat dan waktu yang berbeda pula namun dari aspek eksistensi identitas, hanya dapat dipahami melalui kategori perempuan membentuk subjek dalam serangkaian representasi politiknya. Di mana subjek sebagai aktor yang selalu berkorelasi dengan kekuasaannya. Sebagaimana menurut Butler (1999) dan Foucault (1980) representasi bekerja dalam proses politik yang membutuhkan perluasan visibilitas atau legitimasi subjek secara politis, karena representasi juga dibentuk oleh sistem kekuasaan dari subjek sendiri. Pendapat ini memberikan ruang bagi subjek secara politis dalam ruang dan waktu yang berbeda bagi perempuan dan dapat pula sebagai aktor yang berbeda tidak lagi pasif, tidak berperan di wilayah domestik, berperilaku lembut, cara berpakaian dan lain-lain, tetapi subjek membentuk kesadaran diri dalam diskripsi aktif dan memiliki daya tawar yang diperhitungkan dari pihak lain dalam berbagai domain. c) Konsep Poligami Istilah poligami secara bahasa memberikan pengertian berkenaan dengan praktik peristerian/suami lebih dari satu dalam waktu bersamaan (Hornby, 1990) 4. 4 Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang perempuan memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (group marriage; kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami ditemukan dalam sejarah manusia, namun poligini merupakan bentuk paling umum terjadi (Ensiclopedi Islam dan Umum, 2005) 25 Suatu pandangan hubungan perkawinan yang lebih mengikat tentang poligami, yaitu pandangan Mulia (2004: 43-44) poligami merupakan ”ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersama”. Selain poligami, praktik lain bagi ”istri yang memiliki suami lebih dari satu disebut poliandri dalam waktu yang sama”. Walaupun praktik poliandri tidak banyak dilakukan dan hanya terjadi di dalam tradisi suku-suku tertentu, dan bahkan dalam agama Islam dilarang. Berbeda dengan pembatasan pengertian yang diajukan oleh Muthahhari (1981:9-17) memberikan penegasan dua istilah bentuk perkawinan yang bertentangan, yaitu monogami versus poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang menekankan pada semangat ekslusif yang khusus atau perasaan secara khusus yang bersifat individual, sedangkan poligami kondisi pemilikan bersama atas istri atau suami. Selanjutnya dijelaskan pula bentuk poligami, yang mencakup seks komunal (perkawinan kelompok secara bersama-sama), poliandri, dan poligini. Perkawinan seks komunal merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh beberapa pria bersaudara secara patungan mengawini beberapa wanita bersaudara. Berbeda dengan bentuk poliandri, seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai lebih dari satu suami, sedangkan bentuk lain perkawinan majemuk adalah poligini, seorang pria memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan dengan pembatasan dan persyaratan yang tegas secara syar’i. Uraian bentuk perkawinan tersebut, menjelaskan, bahwa penggunaan istilah poligami yang berkembang di berbagai kajian akademis dan masyarakat luas merupakan bentuk yang kurang tepat, dan sudah menjadi istilah yang umum 26 dipakai dalam berbagai kajian perkawinan. Dengan demikian, penggunaan istilah poligami dalam kajian ini merujuk pada konsep poligini. Poligami dalam masyarakat Islam merupakan persoalan kontroversial di kalangan ahli-ahli hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ashabuni (1980) dan Azzuhaili (1989) bahwa sebagian besar kalangan ahli hukum Islam (jumhur ’ulama) berpandangan atas kebolehan (al ibahah) beristeri lebih dari satu. Namun praktik poligami secara historis sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pra Islam dengan jumlah tanpa batas. Kemudian Islam hadir melalui Nabi Muhammad saw mereformasi dengan pembatasan hanya empat orang isteri, dengan persyaratan dapat berbuat adil. Jika merasa tidak mampu berbuat adil di antara para isterinya, maka diwajibkan beristeri hanya satu atau menikahi budak yang dimilikinya. Praktik poligami ini merujuk al Qur’an (4: 2-3), para ulama (imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan as-Syafi’i) membaca ayat tersebut sebagai kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Berbeda pembacaan yang dilakukan oleh Asad (1980) bahwa poligami dikaitkan dengan ”budak yang dimiliki” merujuk pada perempuan yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu pasangannnya sendiri. Artinya laki-laki untuk tetap mepertahankan pernikahan dengan pasangannya sendiri. Pembacaan Asad ini memberikan pemahaman poligami juga dikaitkan dengan persoalan anak yatim. Lebih jauh, seperti pembacaan yang dilakukan oleh Wadud (1999) selain perlakuan kepentingan anak-anak yatim, juga al Qur’an tidak menyodorkan poligami merupakan solusi bagi pertimbangan ekonomi, kemandulan isteri, atau kebutuhan seksual laki-laki. Sementara al Qur’an hanya mendasarkan pada 27 keharusan untuk menjamin keadilan sosial bagi perlakuan anak-anak yatim perempuan. Pembacaan Barlas (2003) lebih spesifik bahwa poligami dalam al Qur’an tidak merujuk keistimewaan laki-laki atas peluang berpoligami, kebolehannya digantungkan dengan persyaratan-persyaratan yang ketat dan rinci, dan tidak merujuk pada fungsi seksual. Secara faktual, perkembangan masyarakat Islam dewasa ini, bahwa praktik poligami banyak disalahgunakan tanpa melihat bagaimana sesungguhnya latar belakang poligami sebagai solusi di mana kondisi sosial yang tidak normal atau darurat. Dalam perkembangannya memberikan peluang distruktif atas latar belakang praktik poligami di tengah-tengah kehidupan dewasa ini. Bahkan ada anggapan bahwa Islam melegalkan bentuk diskriminasi dan marginalisasi kepada kaum perempuan. Oleh karena itu, kajian tentang poligami harus dikritisi kembali hakikat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, dan antropologis. c. Kontestasi Kekuasaan Konsep kekuasaan merupakan wacana menarik di kalangan ilmuwan sosial. Foucault, misalnya, mengatakan bahwa kekuasaan tidak terbatas pada pihak dominan atau sejenisnya (Eagleton, 1991:7) Berbeda dengan Barthes (1967) yang lebih menekankan pada aspek makna atau bahasa murni yang didasarkan pada elemen-elemen semiology. Sedangkan, bagi Foucault (1980) semua pengetahuan mengoperasikan praktik sosial dalam situasi historisnya; artinya semua pengetahuan adalah kekuasaan. 28 Sejalan dengan itu, pengetahuan tidak terpisahkan oleh relasi-relasi kekuasaan (Foucault, 1980). Wacana menurut definisi ini tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi menuntut pembentukan dalam konteks yang spesifik terhadap relasi-relasi kekuasaan secara spisifik pula atau adanya proses pertarungan ideologis dengan menghadirkan makna ganda, sebab makna selalu merupakan akibat dari tindakan artikulasi, makna harus diekspresikan dalam konteks yang spesifik (Storey, 2007). Formulasi pemaknaan ganda yang secara ideologis bertentangan dan bertarung, dalam relasi pengetahuan inilah sebagai ruang lingkup kontestasi kekuasaan. d. Kekuasaan sebagai Sarana Memperoleh Posisi Sosial Orientasi Bourdieu tentang konsep struktural konstruktivisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ritzer dan Goodman (2010: 578-579), Jenkins (1992), dan Faruk (1994) analisis struktural objektif yang berada pada arena berbeda, tidak dapat dipisahkan dari analisis genesis, dalam individu biologis, dari struktur mental yang pada batas-batas tertentu adalah produk dari perpaduan struktur sosial; yang juga tidak dapat dipisahkan dari analisis struktural ini: ruang sosial dan kelompok yang menguasainya adalah prroduk dari perjuangan historis. Gagasan Bourdieu dalam menjembatani persoalan dikotomi teori dan praktik, agency dan struktur sosial dan lain-lain, diwujudkan dalam beberapa konsep penting, antara lain habitus, arena (ranah/ruang/field), capital, kekuasaan simbolik (symbolic power), dan kekerasaan simbolik (symbolic violence). Penjelasan konsep-konsep tersebut digambarkan sebagai berikut: 29 (www.emiraldinsigh.com diakses 3 April 2013) e. Mekanisme Habitus, Kapital, dan Strategi Kekuasaan Habitus merupakan aspek yang kohesif dalam individu dan kelompok berupa sistem disposisi atau skema persepsi, pemikiran dan tindakan yang didasarkan oleh aturan formal dan aturan-aturan eksplisit dalam waktu yang panjang dan berubah-ubah (Bourdieu, 1990). Disposisi ini didapat dari posisi sosial yang beragam dalam ranah tertentu, dan beradaptasi secara subjektif terhadap posisi tertentu. Perubahan relasi individu dan kelompok oleh Harker, Mahar dan Wilkes (1990) dipandang sebagai tempat dan habitus seseorang yang memproduksi relasi-relasi personal, misalnya dalam bentuk kerjasama, cinta, persaingan, dan juga mengubah kelas-kelas konseptual menjadi kolektifitas nyata. 30 Konsep Habitus tidak dapat dipisahkan dengan konsep arena perjuangan. Kedua konsep tersebut memiliki prinsip hubungan yang saling mengandaikan, hubungan struktur-struktur objektif atau lingkungan (sosialnya) dan strukturstruktur yang terintegrasi dalam diri pelaku (agen individual) (Bourdieu, 1994; Wallace & Wolf, 1995). Selanjutnya konsep arena merupakan ruang untuk memperjuangkan sumber-sumber yang dibutuhkan dan sangat menentukan, karena dalam suatu masyarakat ada yang dikuasai dan menguasai. Dalam hal ini, prinsipnya adalah dominasi sangat tergantung pada situasi, sumber daya, dan strategi pelaku. Bourdieu (1984) mengilustrasikan ranah sebagai arena perjuangan, atau permainan sebagai tempat berlangsungnya pertarungan dan berbagai bentuk strategi untuk mendapatkan berbagai sumber. Dengan kata lain, ranah merupakan suatu sistem posisi-posisi sosial, secara internal dibentuk oleh relasi-relasi kuasa. Konsep habitus dan ranah merupakan konsep alamiah karena saling mengandaikan, hubungan timbal balik antara struktur-struktur bidang sosial dan struktur-struktur yang telah terintegrasi pada individu (Bourdieu, 1998). Konsep arena atau ranah yang diartikan sebagai arena pertarungan atau perjuangan menjadi sangat diterministik karena dalam masyarakat ada yang mendominasi dan didominasi. Praktik dominasi dan subordinasi tersebut oleh Bourdieu dan Wacquant (1992) didiskusikan dalam beberapa bidang, misalnya akademi, ekonomi, keagamaan dan kekuasaan, dan lain-lain. Relasi-relasi kekuasaan dalam masyarakat didasarkan pada pemetaanpemetaan logika posisi sosial dan penguasaan sumberdaya. Artinya setiap kelas sosial didefinisikan dalam hubungan dengan kelas-kelas lain. Dunia sosial oleh 31 Bourdieu (1984) digambarkan dengan bentuk ruang dengan beberapa dimensi yang didasarkan prinsip diferensiasi dan distribusi. f. Kapital sebagai Modalitas Kekuasaan Modal atau capital merupakan logika yang mengendalikan bentuk-bentuk perjuangan. Bagi Bourdieu (1990) modal mencakup sesuatu yang material dan imaterial atau atribut invisibilitas yang mengandung aspek kultural, seperti status, prestise, dan otoritas sebagaimana yang dinamakan dengan modal simbolik. Sementara hal-hal yang bernilai budaya dan pola konsumsi disebut modal budaya, sedangkan modal sosial berupa kekuatan jaringan yang berpengaruh dan membantu individu untuk memperoleh posisi sosial. Setiap tindakan individu adalah produk dari relasi habitus dan ranah, di samping itu, keduanya dibentuk oleh kekuatan-kekuatan lain serta berbagai modal yang dimiliki individu dan bahkan individu yang sedikit modal ataupun tidak memilikinya. Dalam realitas masyarakat, selalu muncul yang menguasai dan dikuasai. Relasi dominasi ini bergantung dengan situasi, sumberdaya dan strategi pelaku. Pemetaan relasi kekuasaan didasarkan pada pemetaan atas kepemilikan dan kompisisi kapital. Kapital simbolik menghasilkan kekuasaan simbolik. Oleh karena itu, kekuasaan simbolik membutuhkan simbol-simbol kekuasaan. Dengan demikian, modal simbolik membutuhkan pengakuan oleh kelompok baik secara institusional maupun bukan institusional (Bourdieu, 1991). Karena setiap ranah menurut Bourdieu (1990) menuntut individu memiliki kekuatan modal agar tetap 32 eksis, mampu bertarung untuk mendapatkan atau mengumpulkan sumber-sumber yang diinginkannya. g. Strategi Kekuasaan melalui Wacana Setiap ranah memiliki struktur-struktur berbeda atau aturan-aturan yang secara konvensional dan terselubung dalam aktivitas sehari-hari, oleh Bourdieu (1991) disebut ”kekerasan simbolik” merupakan legitimasi modal budaya yang memprioritaskan efektifitasnya sebagai sumber kekuasaan dan kesuksesan. Dengan kata lain, bentuk kekerasan yang dipraktikkan pada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, meskipun ada proses-proses yang salah tetapi diterima sebagai sesuatu kewajaran. Sesuatu yang menyakitkan, dalam upaya mengilustrasikan kesuksesan, ketenaran, dan kebahagiaan dirinya, ”kaum perempuan harus menoleh kepada laki-laki untuk bisa menemukan kata yang tepat dan disetujui”(Haryatmoko, 2010:13)5. Dalam hal ini, penguasaan atas wacana menjadi dominasi laki-laki seolah-olah menjadi sesuatu yang wajar atau alamiah dan bahkan sering dianggap benar. Misalnya, Pengarang novel menggunakan wacana poligami untuk pertarungan dengan novel lain dengan isu-isu kebebasan seks di arena sosial, wacana poligami diproduksi dengan berbagai pemaknaan dan latar belakang pelaku yang berbeda. Di satu sisi, wacana menjadi kontroversi di ruang sosial. Di sisi lain, ia bertarung dengan isu-isu seks bebas yang dibangun oleh pengarang lain. Berangkat dari pertarungan wacana ini, sehingga wacana poligami lebih 5 Makalah pernah dipresentasikan di Pasca-Sarjana Sosiologi UI pada tanggal 26 Agustus 2010. 33 mendapatkan keuntungan karena ruang sosial didominasi oleh masyarakat beragama yang cenderung mendukung poligami sebagai ajaran agama. Dengan demikian, dukungan poligami lebih diterima sebagai sesuatu kewajaran dan oleh masyarakat pada umumnya yang menolak wacana seks bebas, walaupun sebagian mereka ada yang menolaknya. Bourdieu (1991) membagi bentuk-bentuk simbolik, berupa bahasa, kodekode pakaian, dan bentuk tubuh. Bentuk simbolik merupakan fungsi kognitif simbol dan fungsi sosial yang berfungsi sebagai instrumen pengetahuan dan keberlangsungan reproduksi tatanan sosial. Dalam kehidupan sosial sering terjadi pertarungan simbolik melalui kekerasan simbolik oleh pihak dominan atas yang terdominasi. Selanjutnya, tindakan-tindakan pengetahuan yang mencakup pengakuan, persetujuan atas doxa dan keyakinan yang merupakan kekerasan simbolik yang dialami oleh perempuan atupun laki-laki. Instrumen-instrumen pengetahuan itu, oleh Bourdieu (1998) dianggap sebagai wujud terbentuknya relasi dominasi. Oleh karena itu, ruang sosial dipahami sebagai medan pertarungan kelompok-kelompok yang memiliki posisi-posisi sosial tertentu dengan menampilkan atribut gaya hidup yang berbeda. Bourdieu (1968) dan Harker, Mahar, dan Wikes (1990) dalam An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, mengemukakan bidang seni dan sastra yang bekerja dalam ranah estetika. Estetika dimiliki oleh kompetensi artistik habitus sastrawan dalam membangun wacana melalui karyanya, berupa modal simboliknya sebagai sarana untuk memperoleh posisi di ruang sosial, atau fungsi-fungsi politis dari berbagai praktik simbolik. 34 Demikian halnya, karya seni merupakan produk budaya yang berkorespondensi dengan kondisi ekonomi, sosial dan sejarah, serta kondisi tersebut selalu beradaptasi. Setiap karya merupakan suatu objek kultural yang diposisikan dalam suatu ranah berbagai relasi kekuatan sosial yang membutuhkan strategi dan perjuangan pengarangnya melalui pembeda (distinction) dalam hal makna dan nilai artistik (Bourdieu, 1984). Pembedaan ini merupakan strategi pertentangan terhadap representasi tradisi yang ada diciptakan sebagai keunikan karya, sebagai modal simbolik dan ekonomi, yang diperjuangkan selalu menyertai aktivitas kreasi dan apresiasinya untuk memperoleh posisi atau status tertentu. Dengan kata lain, kehormatan/reputasi atau status merupakan prinsip dari sistem produksi dan reproduksi yang digunakan sebagai instrumen pelestarian dan peningkatan modal simbolik (Bourdieu, 1998: 69) Selanjutnya untuk memetakan kontradiksikontradiksi di ruang pertarungan atau perselisihan, oleh Baurdieu disebut ranah/medan. Oleh karena konsep ini, dapat membantu mempertajam analisis dan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. 35 h. Kerangka konsep Modal Budaya, sosial, ekonomi, & simbolik Habitus Orientasi normatif (Norma, nilai & keyakinan) Agen sosial sarana Proses perolehan (ketrampilan &sumber kreatifitas), dasar kepribadian, & logika sosial Diskursus PoligamiIntersectionality Kelas sosial & Gender Keadaan situasional (lingkungan sosial) 1.8 Metode Penelitian Dalam sejarah filsafat, Francis Bacon (1561-1625) dan Augus Comte (17981857) meletakkan dasar pengetahuan empiris-analitis melalui rasionalisme dan empiris, merupakan bentuk upaya pembersihan pengetahuan dari kepentingan atau dengan kata lain fakta objektif sebagai pengetahuan yang sahih (Hardiman, 2009). Dalam proses dialektika ilmu pengetahuan alam dan sosial, semangat positivisme menjadi tuntutan bersikap positivistik. Sejalan dengan itu, positivistik memiliki tiga pengandaian yang saling berkaitan. Pertama, prosedur metodologis ilmu alam diimplementasikan dalam ruang lingkup ilmu sosial. Kedua, hasil penelitian diformulasikan dalam bentuk hukum-hukum sebagaimana terjadi di ilmu alam. Ketiga, adanya penyediaan pengetahuan yang bersifat teknis. Keduanya, yaitu 36 ilmu alam dan sosial merupakan ilmu yang bersifat netral atau bebas nilai (Giddens, 1975). Perkembangan selanjutnya, penerapan metode-metode alam pada kenyataan sosial mengandung permasalahan. Hal ini disebabkan oleh pandangan tentang aktifitas-aktifitas individu tidak dapat diposisikan ke dalam bingkai hukum-hukum tetap. Kemudian lahirlah perdebatan tentang metode-metode (methodenstreit), begitu juga ilmuwan ilmu-ilmu budaya para penganut Neo-Kantianisme berpendirian, bahwa ilmu-ilmu budaya menghasilkan relevansi nilai (Hardiman, 2009). Artinya, gejala sosial memilki makna budaya yang hanya bisa dimengerti oleh pemahaman konteks budaya dari objek yang diteliti (Nugroho, 2004). Dalam konteks pemikiran mazhab Frankfurt yang sering dikenal sebagai ”Teori Kritis” lebih menekankan pada sifat dialektis, sebagaimana diungkapkan oleh Geuss (1981) dengan cara dua macam kritik. Pertama, kritik transendental dengan cara menemukan syarat-syarat pengetahuan dalam diri subjek. Kedua, kritik imanen dengan menemukan kondisi sosiohistoris dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia (Hardiman, 2009). Atas dasar argumen ini peneliti memililih wacana kritis Nourman Fairclough sebagai teknik analisis novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Penelitian ini memusatkan kajian pada penelitian kepustakaan yang sifatnya analitis wacana kritis berdasarkan kajian teks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah culture studies, yaitu suatu pendekatan yang menganggap budaya bersifat politis dalam pengertian yang sangat spesifik, yaitu sebagai ranah 37 pergumulan dan konflik. Artinya adanya proses pertarungan ideologis dengan menghadirkan makna ganda, makna selalu merupakan akibat dari tindakan artikulasi, sebab makna harus diekspresikan dalam konteks yang spesifik (Storey, 2007). Dalam hal ini, kajian dipusatkan pada teks sastra dan wacana poligami sebagai produk dan praktik budaya dewasa ini. a. Data dan Sumber Data a) Sumber Primer Sumber primernya, berupa naskah novel Ayat-Ayat Cinta sebagai modal simbolik seorang sastrawan. Teks novel sebagai data primer berupa teks naratif merupakan sebuah fakta semiotik yang dipandang sebagai suatu tanda jika mewakili dan atau mengacu sesuatu yang lain. Secara garis besar teks naratif dibedakan dalam dua unsur, yaitu cerita dan wacana. Unsur cerita merupakan isi, tetapi wacana merupakan ekspresi. Oleh karena, dengan dua unsur ini belum dianggap memadai untuk menangkap semua elemen situasi komunikasi. Dalam hal ini, unsur cerita dirinci dengan subtansi isi atau inti masalah, bentuk isi (peristiwa berupa aksi, kejadian dan eksistensi berupa aktor, serta latar), subtansi ekspresi (keseluruhan semesta baik nyata maupun imajinasi) dan bentuk ekspresi, sedangkan unsur wacana terdiri dari bentuk wacana yang mencakup struktur transmisi naratif (susunan, modus, sudut pandang) dan subtansi wacana berupa media, dan sarana untuk berkomunikasi atas gagasannya (Nurgiyantoro, 2009). Selain data dari novel Ayat-Ayat Cinta di atas, pandangan para pelaku poligami yang merepresentasikan kelas sosial atas dan bawah. 38 b) Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Misalnya pendapat tokoh tentang poligami yang dipublikasikan melalui majalah, internet, ataupun tabloid. b. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah metode baca. Metode baca digunakan untuk mengidentifikasi data yang berupa teks naratif. a) Metode Baca Teknik pengumpulan data dilakuan dengan menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam karya sebagai subjek dengan cara digali data pribadi dan dari bentuk-bentuk ketidaksetaraan/kekerasan yang dialami oleh perempuan beserta latar belakang kehidupannya. Data dikumpulkan dengan metode baca, yaitu membaca secara cermat novel Ayat-Ayat Cinta. Hasil baca data kemudian dipindahkan atau dicatat ke dalam kartu atau ke dalam tabel. Selanjutnya data diklasifikasikan menurut aspek-aspek yang menjadi sarana pendukung wacana. Kriteria yang dijadikan pedoman untuk merepresentasikan gender, adalah (1) perilaku, kegiatan, pemikiran perempuan dan laki-laki, (2) subordinasi dan dominasi yang dialami perempuan. Selanjutnya, untuk merepresentasikan kelas sosial, adalah merujuk pada perilaku, kegiatan, pemikiran individu atau kelompok kelas bawah dan kelas yang tinggi dalam suatu komunitas. 39 b) Metode Dokumentasi Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi data pendukung atau sekunder, meliputi biografi pengarang, pendapat tokoh tentang poligami yang dipublikasikan melalui, surat kabar majalah ataupun tabloid, internet dan berbagai keputusan ormas keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan Persis). Untuk memudahkan tugas itu, digunakan search engine untuk pengumpulan data yang tersedia dalam alamat Website. c. Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough (2001), analisis ini berusaha menghubungkan teks yang mikro dengan konteks sosial yang makro. Fokus perhatiannya, adalah bahasa ditempatkan sebagai praktik sosial. Untuk melihat ideologi pengarang digunakan analisis bahasa secara menyeluruh, karena bahasa dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk tindakan dalam hubungannya dengan dialektika dengan struktur sosial. Oleh karena, pusat perhatian analisis ini, adalah bagaimana bahasa diproduksi dan direproduksi dari relasi sosial dan konteks sosial. Model yang dibangun oleh Fairclough (1992) dalam analisisnya di samping dimensi linguistik, adalah ia mengintegrasikan pemikiran sosial, politik menjadi bagian integral dari perubahan sosial. Pemakaian bahasa dalam wacana merupakan bentuk praktik sosial yang memiliki implikasi, antara lain wacana merupakan suatu bentuk tindakan dan bentuk representasi dalam memandang realitas sosial, dan hubungan interaksional antara wacana dan struktur sosial. 40 Wacana dibagi dengan struktur sosial, kelas, perjuangan sosial dan relasi sosial berhubungan relasi-relasi tertentu (Fairclough, 2001). Kemudian ia memperkenalkan tiga tahap untuk melakukan penelitian dengan metode analisis wacana kritis. Tiga tahap tersebut, adalah deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi dalam menghubungkan teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, yakni socio-cultural practice. Ada tiga dimensi yang dilakukan Fairclough dalam analisisnya, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural, sebagai berikut: a) Teks Level pertama berupa teks dianalisis secara linguistik, atau deskripsi perhatiannya pada beberapa aspek struktur bahasa, yaitu aspek kosa kata dan gramatika, dan struktur tekstual. ( a) Kosa kata Kosa kata mencakup nilai-nilai eksperensial yang menjelaskan kata-kata ideologis, kelebihan kata atau penyusunan kata kembali, hubungan makna yang mencakup sinonim, hiponim dan antonim. Penekanan pada nilai-nilai relasional, misalnya ungkapan-ungkapan eufemisme, ironi, formal atau informal, dan lainlain. Kosa kata ini, memberikan pilihan kata sebuah teks yang menciptakan hubungan sosial antar partisipan, yaitu antara pembuat teks dengan pembacanya. Kosa kata yang berhubungan nilai-nilai ekspresif. Kosa kata yang menunjukkan pada evaluasi positif atau negatif sesuatu yang berhubungan dengan ideologi pengarang dalam bentuk penggunaan metafora. 41 b) Gramatika Aspek-aspek gramatika yang berhubungan dengan nilai-nilai eksperensial, adalah tipe-tipe proses dan partisipan yang dominan, situasi agen tampak jelas atau tidak, proses-proses situasi yang tampak, penggunaan kalimat aktif atau pasif, dan kalimat positif atau negatif. Aspek-aspek gramatika yang berkaitan dengan nilai-nilai relasional, adalah model-model pertanyaan yang digunakan, relasi-relasi modalitas, dan penggunaan kata ganti. Selanjutnya aspek-aspek gramatika yang berhubungan dengan nilai ekspresif, misalnya aspek-aspek penting modalitas; memberikan petunjuk tentang sebuah peristiwa. Hubungan antar kalimat sederhana juga diperhatikan, misalnya penggunaan jenis kata penghubung logis, penggunaan kalimat kompleks bersifat koordinasi atau subordinasi, arti atau makna yang digunakan dalam menghubungkan teks ataupun luar teks. c) Struktur teks Struktur teks ini yang diakji tiga unsur adalah, pertama kaidah-kaidah interaksional. Aspek yang diperhatikan dalam struktur teks berkaitan dengan penggunaan kaidah-kaidah interaksional. Kedua, ukuran struktur yang dimiliki teks. Teks dirumuskan atas dasar urutan kepentingannya, maka teks dapat menunjukkan evaluasinya atas apa yang layak ditampilkan. Aspek kelayakan tampilan tersebut harus mendapatkan perhatian dalam ranah deskripsi. 42 b) Praktik wacana Level kedua berupa Praktik wacana, atau interpretasi (Fairclough, 2001) berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi teks (Fairclough, 1995a). Menurut Fairclough, fitur level kedua ini mengekapulasi prinsip-prinsip penting dalam wacana kritis, yang mana analisis teks tidak dapat dipisahkan (ekslusi) dari praktik institusi dan wacana pada domain suatu teks. Atas dasar kerangka kerja ini, interdiskursivitas atau tatanan wacana, mengkaji tentang bagaimana teks novel diproduksi, direkontekstualisasi, dan berdialog dengan teks lain atau intertekstual (Fairclough, 2003). Pada level praktik wacana ini ada yang dihilangkan, yaitu aspek distribusi dan konsumsi teks dengan lebih memfokuskan pada aspek bagaimana suatu teks diproduksi, sebagaimana Fairclough (1995a) melakukan pengabaian tersebut. Selanjutnya, Tahap ini, oleh Fairclough (2001) teks akan dilihat keterkaitannya sebagai konteks situasional dan intertekstual yang mencakup enam dimensi yang berhubungan secara paralel, yaitu seperti halnya diilustrasikan dalam skema di bawah ini: 43 Prosedur interpretasi/MR Sumber-sumber Tatanan sosial Penginterpretasian/interpreting Konteks situasional Sejarah interaksional Konteks intertekstual Fonologi gramatika, kosa kata Bentuk luaran ujaran Semantik,pragmatik Pemaknaan ujaran Kohesi, pragmatik Koherensi lokal Skemata Struktur teks dan poin Bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa tahap pertama berhubungan dengan konteks interpretasi berusaha melihat keterkaitan teks dengan konteks intertekstualitasnya. Tahap kedua, berhubungan dengan empat tingkatan interpretasi teks menunjukkan aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk melihat konteks situasional. Namun bentuk luaran ujaran tidak diperhatikan karena sudah dilakukan dalam tahap analisis deskripsi teks. Sedangkan, pemaknaan (utterance) bergantung pada pemaknaan ujaran (semantik dan pragmatik), sedangkan koherensi lokal untuk memahami lokal dalam teks. Selanjutnya, struktur teks dan poin tergantung pada schemata, yang ada kemiripan dengan deskripsi, tetapi pada tahap struktur teks yang lebih besar, schemata yang dimaksud adalah tidak sebatas 44 melihat bagaimana suatu teks dieksplorasi dalam paragraf, namun bagaimana suatu teks merumuskan suatu subjek tertentu. c) Praktik sosiokultural Level ketiga berupa praktik sosiokultural, atau eksplanasi (Fairclough, 2001). Tujuan tahap ini untuk mendiskripsikan diskursus sebagai proses sosial, menjelaskan bagaimana diskursus menjadi diterminan bagi struktur sosial, dan efek reproduksi diskursus berupa mempertahankan atau mengubahnya. Dengan demikian, fokus pada level ini, adalah relasi kekuasaan, proses dan praktik sosial yang difokuskan pada proses dan praktik usaha sosial. Artinya pengamatan diskursus merupakan bagian dari proses usaha sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan. Level yang harus mendapatkan penekanan tentang efek sosial diskursus maupun penentu sosial diskursus dikaji melaui tiga level organisasi, yaitu level masyarkat, level institusi, dan level situasi diilustrasikan dalam gambar dibawah ini: Kemasyarakatan Kemasyarakatan (societal) Institusional MR Diskursus MR Institusional Penentu situasional Efek-efek situasional (situational determination) 45 Diagram di atas, menentukan asumsi bahwa diskursus memiliki ketentuan-ketentuan dan efek pada semua level di atas, meskipun level societal dan institutional akan secara jelas lebih membedakan tipe-tipe institusi diskursus, dan apapun diskursus dibentuk oleh relasi kekuasaan institusi dan kekuasaan masyarakat, serta memberikan kontribusi pada usaha/perjuangan institusi dan masyarakat. 1.9 Sistematika Pembahasan Pembahasan penelitian disertasi ini mencakup beberapa bab sebagai berikut. Bab I: Pendahuluan meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II: Kelas Sosial, Gender, dan Poligami. Mengkaji kondisi perempuan Arab pra Islam, reduksi praktik poligami di era permulaan sejarah Islam di Arab, relasi gender dan kelas sosial masyarakat Arab; relasi gender di masyarakat Arab, kelas sosial masyarakat Arab. Historis defacto poligami atau pergundikan di Indonesia, wacana poligami di kalangan ulama fiqh, pembacaan poligami di era kontemporer, konsep kesetaraan gender dalam pandangan al-Qur’an; habitus, agensi dan kesetaraan, hubungan keimanan, kelas sosial dan kesetaraan, dan pernikahan di dalam Islam. Bab III: Analisis Tekstual. Mengkaji nilai-nilai eksperensial, relasional dan ekspresif teks novel Ayat-Ayat Cinta dalam kekerasan rumah tangga, 46 pemukulan kepada pemerempuan, kekerasan di bidang hukum, kesetaraan perempuan berlatar belakang German, gagasan patriarki, kelas sosial dan modal ekonomi, kelas sosial dan modal budaya, dan pemaknaan poligami. Bab IV: Analisis Praktik Wacana: wacana poligami: kekerasan sosial, wacana kesetaraan, wacana suami sebagai imam, wacana kelas sosial atas dan modal budaya, dan pemaknaan poligami Bab V: Analisis Praktik Sosio-kultural. Mengkaji persimpangan kelas sosial dan gender dalam poligami, meliputi: kekerasan dalam ranah sosial, pemukulan istri, hukum dan tuduhan pemerkosaan, peminangan, kepemimpinan atas modalitas dan gaya hidup, reputasi dan status sosial, darurat dan kebolehan berpoligami. Interelasi sosio-kultur poligami dalam konteks masyarakat Indonesia, kontekstualisasi wacana poligami, dan posisi sosial pengarang. Bab VI Kesimpulan dan Saran Daftar Pustaka Glosarium