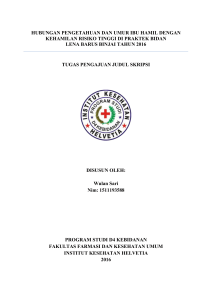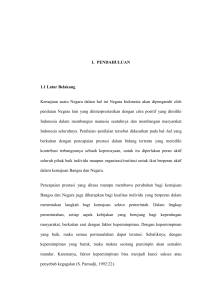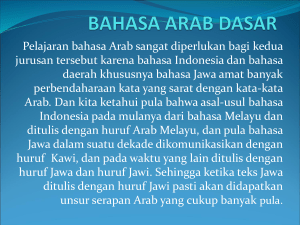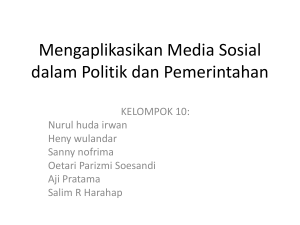Membaca Hasrat Politik Islam Nusantara
advertisement

Membaca Hasrat Politik Islam Nusantara DISKURSUS tentang penetapan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, sepertinya belum selesai didiskusikan. Kebijakan ini sendiri juga mendapatkan penolakan dari kaum intelektual-akademisi. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab penetapan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara dilakukan tanpa kajian ilmiahakademik yang memadai, sehingga cenderung “menistakan” tradisi akademik yang selama ini dikembangkan dalam kajian sejarah di perguruan tinggi. Itu sebab, pakar sejarah Nasional, Prof Azyumardi Azra dalam Seminar Nasional yang diselenggaraan di Pascasarajana UIN Ar-Raniry beberapa waktu lalu menyimpulkan, bahwa penetapan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara merupakan penyesatan sejarah (Serambi, 15/5/2017). Azyumardi Azra melihat diskursus soal “Titik Nol Islam Nusatara” ini tidak bisa dilepaskan dari kaidah-kaidah dan tradisi ilmiah. Bukti-bukti sejarah dan temuan para pakar, sebagaimana kesimpulan dalam Seminar Titik Nol Islam Nusantara di Pascasarjana UIN Ar-Raniry, sama sekali tidak ada yang menyimpulkan Barus sebagai titik nol (awal mula) islamisasi Nusantara. Seluruh catatan para sejarawan menempatkan Peureulak dan Pasai sebagai titik nol Islam Nusantara, sebagaimana disampaikan Prof Azyumardi Azra dan Prof Farid Wajdi Ibrahim. Plus, kemudian ditambah hasil temuan baru Dr Husaini Ibrahim dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang melihat Lamuri di Aceh Besar sebagai titik nol Islam Nusantara. Oleh sebab itu, penetapan Barus, sebuah Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sebagai Titik Nol Islam Nusantara oleh Presiden Jokowi mau tidak mau harus dilihat dari kacamata ideologi politik. Artinya, kebijakan Jokowi tersebut sarat dengan hasrat kepentingan politik rezim. Jadi, sampai di sini, rasanya kita sulit menolak fakta kepentingan politik semacam ini. Dengan demikian, tulisan saudara Ramli Cibro (RC) berjudul Memetakan Narasi Islam Nusantara (Serambi, 16/5/2017) yang “membenarkan” penetapan Barus sebagai titik Nol Islam Nusantara adalah patut dikritisi. Argumentasi utama RC adalah melihatnya dari perspektif awal mula ekspansi ajaran Teo-sufi ke Nusantara yang bersumber dari atau dikembangkan oleh Hamzah Fansuri. Bukan diskursus historis RC bisa saja mengatakan diskursus Titik Nol Islam nusantara hanyalah sekadar tranformasi pemikiran Teo-sufi dan bukan diskursus historis, sehingga justru “sepakat” atas kebijakan Presiden Jokowi yang ahistoris, sebagaimana disimpulkan Azyumardi Azra bahwa Barus bukan titik nol Islam Nusantara. Alhasil, pemahaman RC seperti ini akan sangat rancu, karena bagaimana mungkin kaidah-kaidah sejarah dalam tradisi akademik-ilmiah harus dicabut dari sebuah kebijakan bersejarah tentang sesuatu yang juga identik sepenuhnya dengan sejarah penting masa lalu. Pada titik ini, kesimpulan dari tulisan RC nampak seperti ingin “memaksa” bahwa titik nol Islam Nusantara memang harus dari Barus, meskipun harus menabrak tradisi akademik-ilmiah. Apalagi, kesimpulan RC semacam ini juga diperkuat dengan narasi RC bahwa “Islam Sufistik adalah Islam yang lebih mengedepankan esensi dan substansi dari pada sekadar atribut, perangkat dan simbol semata”. RC menyimpulkan model Islam inilah yang tersebar di Nusantara. Narasi parsial RC seperti ini tentu patut ditanggapi. Sebab, Islam yang diterima di Nusantara bukanlah hanya esensi dan subtansi Islam, melainkan juga atribut, perangkat dan juga sekaligus simbol. Sebab, Islam adalah perpaduan substansi dan juga simbol. Dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dengan sangat mudah kita akan menemukan adanya perkembangan bahasa Arab dan Jawi (Arab-Melayu) sebagai simbol penyebaran Islam. Bahkan, peran fundamental bahasa ini dalam islamisasi Nusantara ini dicatat oleh Prof Naquib al-Attas sebagai keberhasilan yang mengalahkan pencapaian Hindu-Budha. Karena mereka berhasil mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan di kepulauan Nusantara (al-Attas, Historical Fact and Fiction, hal. xvi). Juga seperti dijabarkan oleh TA Sakti dalam artikelnya Bahasa Melayu Pasai, Akar Tunjang Bahasa Nasional Indonesia (Serambi, 19/5/2013), bahwa “bahasa Melayu Pasai berkembang pada masa Kerajaan Samudra Pasai (1250-1524 M). Kerajaan ini amat berperan dalam penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Melaka dan Jawa. Bersamaan berkembangnya agama Islam itu tersebar pula bahasa Melayu Pasai di wilayah tersebut melalui kitab-kitab pelajaran agama Islam yang menggunakan bahasa Melayu Pasai sebagai pengantarnya”. Selain bahasa sebagai simbol penyebaran Islam, juga terdapat atribut dan perangkat lainnya, seperti masjid, kalender hijriah (penanggalan Islam), batu nisan dan sebagainya yang ke semua atribut atau simbol ini berperan maksimal dalam penyebaran Islam di Nusantara. Maka dengan demikian, penetapan Barus sebagai titik Nol Islam Nusantara bukan saja mengangkangi kaidah-kaidah dan tradisi ilmiah-akademik, melainkan juga akan terbantahkan meskipun kita melihat posisi Barus dari perspektif ekspansi ajaran teo-sufisme sebagaimana dikehendaki RC. Apalagi, ajaran Sufi yang berkembang di Nusantara pun sebenarnya cukup beragam, seragam perpaduan berbagai pola dan metode islamisasi yang dijalankan para ulama saat itu. Hasrat politik Kita kembali ke fokus utama tulisan ini, sesungguhnya aroma hasrat dan kepentingan politik dalam penetapan Barus sebagai titik Nol Islam Nusantara sama sekali tidak bisa dihindari. Apalagi, saat meresmikan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara, dengan sangat jelas Presiden Jokowi mendorong agar agama dipisahkan dari politik. Mencermati terjadi gesekan-gesekan dalam kecil Pilkada, Presiden meminta tidak ada pihak yang mencampuradukkan politik dan agama. “Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” kata Jokowi (Kompas.com, 24/3/2017). Meskipun setelah muncul protes dari banyak tokoh Islam lalu kemudian Presiden Jokowi meralat pidatonya ini pada keterangan berikutnya. Namun yang jelas, aroma kepentingan politik dalam menetapkan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara sudah terlanjut terbaca dengan baik oleh publik. Apalagi, saat itu juga sedang berlangsung proses suksesi Pilkada DKI Jakarta, di mana partai politik yang menaungi Presiden Jokowi, yaitu PDIP, merupakan partai utama yang mengusung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan, Ahok lalu diprotes oleh umat Islam dengan aksi unjuk rasa besar-besaran karena terbukti melakukan penistaan agama Islam. Sangat sulit diingkari bahwa kebijakan Presiden Jokowi soal Barus tidak terkait dengan kepentingan politik, baik untuk skala ibu kota dan wilayah lainnya, atau bahkan juga untuk kepentingan Pilpres 2019 nanti. Kesimpulan bacaan saya seperti ini kemudian semakin meyakinkan saya setelah mendengar pemaparan para narasumber pada Seminar Nasional di Pascasarjana UIN Ar-Raniry beberapa waktu lalu, yang menyimpulkan bahwa ada kepentingan ideologi politik dalam kebijakan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara. Kebijakan tersirat yang terbaca, umat Islam hendak diarahkan untuk tidak menempatkan Islam sebagai parameter dalam mengambil kesimpulan dan kebijakan politik, sehingga partai-partai sekuler semakin mudah meraih kekuasaan di republik ini yang berakibat Islam dan kaum muslimin semakin terpinggirkan. Di sini, Barus hendak dijadikan sebagai landasan historis dan referensi “gerakan politik tanpa agama” dengan mencoba menyandarkan pemikiran tersebut ke Teo-sufisme yang berkembang di Barus saat itu, meskipun sandaran itu juga tidak tepat. Jika Barus dulu adalah bagian dari Aceh, maka harus dipahami bahwa sejarah ideologi politik Aceh adalah tercermin dalam kitab Mir’atutullab karya Syiah Kuala yang mengintegrasikan Islam dan politik. Dan, di masa Syiah Kuala (sebagai Qadhi Malikul `Adil), Aceh menjadi “kiblat” peradaban muslim Melayu. Wallahu a’lam bish-shawab. Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2017/08/10/membaca-hasrat-politik-islam-nusantara/ Senin 21 Agustus 2017 | 14:49