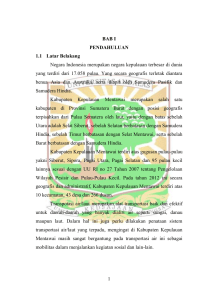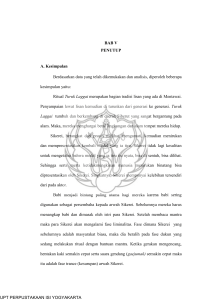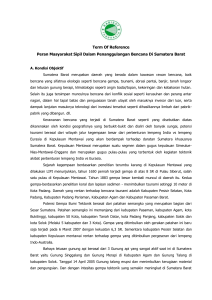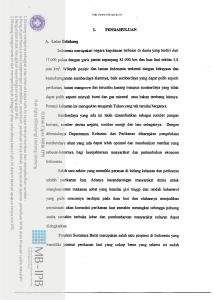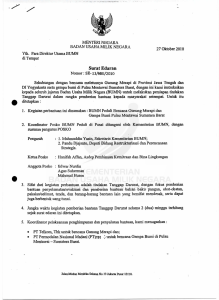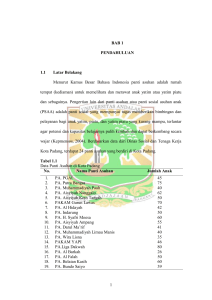BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Penelitian
advertisement

BAB I
PENGANTAR
A. Latar Belakang Penelitian
Indonesia sebagai negara majemuk dengan masyarakat yang tidak hanya terdiferensiasi
ke dalam struktur dan kelas sosial, tetapi juga agama dan etnisitas. Isu etnisitas menjadi
penting dalam diskusi pluralitas ini, karena masing-masing etnik berupaya menunjukkan
eksistensi etnisitasnya. Dewasa ini, hampir semua kelompok etnik telah terkoneksi secara
global, tanpa kecuali pedalaman Pulau Siberut yang selama ini diwacanakan sebagai daerah
‘terisolir’ dan ‘tertinggal’. Di sisi lain, globalisasi mendapatkan perlawanan dari kelompok
etnik minoritas dengan munculnya ke permukaan melalui penanda-penanda lokalitas tertentu
sebagai akibat dari adanya globalisasi itu sendiri (Kleden-Probonegoro, 2002). Berbagai
perlawanan tersebut dimungkinkan oleh adanya perkembangan komunikasi dan informasi
global, sehingga proses reproduksi lokalitas juga bersifat global (Appadurai, 2005).
Globalisasi sebagai gejala yang universal menimbulkan respons terhadap menguatnya
identitas lokal, dan sebaliknya isu-isu globalisasi yang marak memunculkan sikap bagi
pendukung etnik tertentu untuk menampilkan identitas1 mereka (Kleden-Probonegoro, 2002;
Eindhoven, 2002). Penguatan identitas ini muncul diantaranya melalui peneguhan kembali
(revitalisasi) nilai-nilai lokal, meskipun dalam bentuk dan cara yang berbeda.
Penguatan identitas pada suku bangsa Dayak misalnya, sebagaimana yang
digambarkan Maunati (2004) banyak dilakukan melalui promosi pariwisata di Kalimantan
Timur yang didominasi ikon-ikon Dayak. Padahal sebelumnya, orang Dayak lebih dipandang
oleh orang luar sebagai suku ‘liar yang ganas’ (Weintré, 2004: 6), atau sebagai ‘pemakan
orang’, ‘primitif’, ‘bodoh’, dan ‘kotor’ (Djuweng, 1996: 6), maupun sebagai pemburu kepala
yang hidup secara komunal dari berburu dan meramu, dan tinggal di rumah-rumah panjang
(Maunati, 2004: 6). Konstruksi-konstruksi orang luar tersebut didasari penilaian etnosentris,
sekalipun mereka mendasarkan pandangannya pada hal-hal yang eksotik, seperti praktik
hidup komunal yang menjadi bagian dari identitas utama mereka. Pandangan demikian juga
ditujukan orang luar pada kelompok etnik Mentawai.
1
Identitas atau identity menurut kamus Stanford Encyclopedia of Philosophy berasal dari bahasa Latin yang
berarti kesamaan ('sameness').
Anggapan-anggapan yang diberikan oleh orang luar, khususnya dari kelompok mainstream untuk kelompok minoritas seperti Dayak dan Mentawai, sejak masa kolonial sampai
pemerintahan Orde Baru, bahkan hingga saat ini masih sering terjadi. Citra yang diberikan
oleh orang luar itu lama-kelamaan pun diikuti oleh kelompok minoritas. Orang Mentawai
akhirnya mengidentifikasi diri mereka seperti yang dicitrakan orang luar (Delfi, 2005), yakni
orang ‘terbelakang’, ‘kuno’, ‘primitif’ dan ‘tertinggal’. Citra demikian pun diadopsi orang
Mentawai untuk menilai kelompok Mentawai lainnya, karena mereka menganggap
kelompok mereka sendiri lebih ‘maju’. Anggapan demikian masih tetap dibangun dan
disebarkan di antara orang Mentawai dalam relasinya dengan etnik lain maupun antar sesama
kelompok di Mentawai.
Orang Mentawai sering melontarkan ungkapan-ungkapan tertentu terkait citra mereka
dalam perbincangan sehari-hari di Siberut, seperti: “enungan Simattawai, malutlut, malotik”
(jalannya orang ‘Mentawai’, licin, kotor), “katna Simattawai, kapurut, mapusuk”
(makanannya orang 'Mentawai', kapurut (sagu yang dimasak dengan daun sagu) hitam) atau
“leppeina Simattawai, leppei ka rombengan” (bajunya orang 'Mentawai', baju bekas).
Ungkapan demikian sekilas menunjukkan apa yang dimiliki dan dipraktikkan orang
Mentawai merupakan sesuatu yang ‘rendah’ dibandingkan dengan orang luar (Sasareu).
Oleh karena itu, sebagian orang Mentawai masih merasa ‘malu’ untuk menyebut nama 'khas'
Mentawai mereka di depan Sasareu, dibanding nama luar mereka.2
Munculnya nama 'luar' (oni ka Sasareu) bagi orang Mentawai berkaitan erat dengan
proyek keagamaan, baik Kristen (Katolik/Protestan) maupun Islam. Memeluk salah satu dari
agama resmi tersebut, ditunjukkan dengan menyandang nama 'luar’ sesuai agama luar (arat
Sasareu) yang dianut. Dewasa ini untuk memastikan apakah seorang Mentawai memeluk
agama Islam atau Kristen, pada kenyataannya tidak bisa hanya melalui identifikasi nama
‘luar’ mereka. Tidak jarang orang Mentawai yang memakai nama berciri khas Kristen tetapi
mengaku beragama Islam3, maupun sebaliknya.4 Selain nama depan yang diperuntukkan
2
3
4
Orang Mentawai membedakan nama Mentawai (oni ka Mattawai) dari "nama luar" (oni ka Sasareu). "Nama
luar" ini pada awalnya merujuk pada nama 'permandian' yang dipakai pemeluk agama Kristen atau namanama yang berasal dari Bahasa Arab sebagai penanda keislaman. Dewasa ini generasi muda Mentawai
cenderung lebih suka menggunakan nama-nama 'asing' atau adaptasi nama-nama serupa itu.
Misalnya nama-nama Stephanus, Carlo, dan Jonas juga dipakai oleh orang yang beragama Islam, sementara
nama-nama seperti, Akbar dan Salim juga dipakai oleh mereka yang beragama Kristen.
Bandingkan dengan Muslim Bali di Pegayaman sebagaimana dipaparkan oleh Budiwanti (2003: 47-48),
untuk memudahkan pengidentifikasian anak-anak mereka dilakukan dengan pemberian nama-nama urutan
pada anak, seperti Wayan, Nyoman, Nengah dan Ketut, kemudian diikuti oleh nama ke dua seperti namanama nabi, dan sahabat nabi. Adapun nama yang paling penting adalah nama ke dua yang bermakna religius
dan sekaligus sebagai identitas Muslim mereka setelah nama pertama yang merujuk pada identitas Bali.
2
bagi individu, apakah itu oni ka Mattawai atau oni ka Sasareu, baik itu yang bercirikan
Kristen atau Islam, seseorang juga memiliki nama belakang sebagai nama klen (oni uma)5.
Nama klen menjadi penting karena sebagai penanda bagi mereka untuk mengenal dan
mengetahui dari klen mana seseorang berasal.6 Identitas klen yang askriptif ini sudah
diperoleh ketika seseorang terlahir sebagai anggota uma tertentu. Penggunaan oni uma
tersebut secara ideal dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang
se-uma. Oleh karena itu, identitas uma merupakan hal penting dalam relasi dengan sesama
orang Mentawai.
Masing-masing uma di Siberut selalu merujuk pada nenek moyang patrilineal. Oleh
karenanya uma selalu dikaitkan dengan wilayah asal tertentu. Sebelum adanya relokasi
pemukiman di Siberut, uma pada umumnya berada di sekitar lembah sungai dan memiliki
satu bangunan komunal yang juga disebut uma. Jika terjadi konflik yang tidak dapat
diselesaikan dalam uma, sebagian anggotanya akan meninggalkan daerah lembah itu untuk
pindah ke tempat lain dan mendirikan uma baru. Uma ini yang menjadi pusat berbagai
praktik ritual kelompok dan menjadi hal penting dalam kehidupan orang Mentawai (Loeb,
1929; Coronese, 1986; Schefold, 1985a, 1985b, 1988, 1991; Ermayanti, 1989; Zakaria, 1996;
Roza, 1997; Reeves, 2000; dan Rudito, 2005). Praktik ritual uma sebagai lokalitas adalah
untuk membedakan diri dari yang lain, dan praktik ini merupakan bentuk peneguhan akan
identitas mereka. Kehidupan komunal uma beserta praktik ritualnya menjadi penanda bagi
lokalitas Mentawai.
Ke-Mentawai-an sebagai penanda identitas ini terkait dengan apa yang menjadi milik
'kita', bukan milik 'mereka'. Dalam usaha meneguhkan identitas tersebut, orang Mentawai
mencari-cari atau memunculkan ‘kekhasan’ yang pada akhirnya dapat diklaim sebagai
‘milik’ Mentawai. Untuk peneguhan itu pula orang Mentawai mencari model pemerintahan
tersendiri. Hal ini dipicu oleh model pemerintahan Nagari7 yang diberlakukan kembali di
Sumatera Barat. Nagari bukan milik orang Mentawai, melainkan milik orang Minangkabau,
lalu apa model pemerintahan yang dapat diklaim sebagai milik Mentawai? Elit terpelajar
Mentawai memunculkan nama laggai untuk menyebut sistem pemerintahan setingkat desa di
5
6
7
Setelah masuk agama resmi maka orang Mentawai memiliki dua nama, yaitu nama Mentawai (oni ka
Mattawai) dan nama luar menurut agama (oni ka Sasareu).
Misalnya ada orang yang bernama Stephanus Samalelet, maka berarti Stephanus tersebut berasal dari uma
Samalelet, jika dia bernama Stephanus Sajijilat maka berarti dia berasal dari uma Sajijilat. Bila orang yang
bernama Stephanus Samalelet tersebut datang ke kampung lain maka orang-orang di kampung tersebut yang
bernama uma Samalelet adalah kerabat seuma. Stephanus Samalelet tidak boleh kawin dengan perempuanperempuan yang bernama uma Samalelet karena berasal dari uma yang sama.
Nagari adalah bentuk pemerintahan terendah khas etnik Minangkabau setingkat desa.
3
Mentawai. Ide mengenai bentuk pemerintahan laggai ini pernah digulirkan sebelumnya
melalui rancangan peraturan daerah laggai namun ditolak oleh orang Siberut (Delfi, 2005).
Penolakan terhadap sistem pemerintahan laggai berawal dari penggunaan kata laggai
itu sendiri yang memiliki perbedaan makna di Mentawai. Di Pulau Sipora dan Pagai, kata
laggai diartikan sebagai kampung. Di Pulau Siberut, kata tersebut diartikan sebagai ‘alat
kelamin’8 atau ‘batu’ (Delfi, 2005: 201). Perbedaan makna yang muncul dalam wacana
tersebut disebabkan adanya perbedaan dialek yang berkaitan dengan wilayah asal. Klaim
daerah asal menjadi bagian dalam perbincangan identitas, dan mengetahui asal-usul
seseorang merupakan hal yang penting guna membangun relasi sosial. Untuk mengetahui
asal-usul seseorang, orang Mentawai Siberut memiliki nama untuk menyebut kampung asal
nenek moyang mereka, yakni ‘pulaggajat’. Di Siberut, pada umumnya jika ingin mengetahui
asal seseorang, pertanyaan yang diajukan adalah: "Kaipa pulaggajatnu?". Berbeda halnya
dengan di Sipora dan Pagai, apabila menanyakan dari mana seseorang berasal dengan
pertanyaan: "Kaipa laggainu?". Di Siberut umumnya pertanyaan Kaipa laggainu? dianggap
sebagai pertanyaan yang ‘tidak pantas’ diajukan, karena sebagaimana sudah disebutkan di
atas bahwa kata laggai dimaknai sebagai alat kelamin atau batu, bukannya dimaknai
kampung atau daerah asal.
Perbedaan makna itu dijadikan alasan utama oleh orang Siberut dalam penolakan
Ranperda Laggai sehingga kata laggai dianggap 'tidak cocok', 'tidak pantas', karena
bermakna ‘kotor’ dan sekaligus ‘kuno’(Delfi, 2005: 219). Pertentangan makna itu
mengakibatkan laggai belum dapat dijadikan nama untuk pemerintahan terendah di
Mentawai. Selama hampir 10 tahun menjadi daerah otonom, Mentawai belum mampu
menyepakati nama untuk pemerintahan terendahnya. Perbincangan laggai kembali
mengemuka setelah munculnya Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 berkaitan
dengan pemberlakuan nagari di seluruh wilayah Sumatera Barat. Ini memunculkan
penolakan dari orang Mentawai, khususnya dari kelompok elit terpelajar yang sebelumnya
telah mengusung ide laggai. Kondisi ini mengakibatkan istilah laggai yang sudah ditolak itu
8
Di Siberut sendiri kata laggai umumnya memiliki dua pengertian yaitu; batu dan alat kelamin (buah zakar).
Dewasa ini dalam perbincangan sehari-hari orang Siberut lebih sering mengemukakan bahwa arti kata laggai
itu ‘kotor’, berarti lebih sering diartikan sebagai alat kelamin atau kemaluan dari pada batu. Dengan
demikian, bagi orang Mentawai Siberut kata laggai dipandang sebagai kata yang memalukan atau 'kotor'.
Penggunaan kata laggai untuk menggantikan desa pada akhirnya akan memunculkan istilah-istilah ‘kotor’
lainnya misalnya, kepala desa (ute’ laggai) diterjemahkan sebagai kepala kemaluan. Jika laggai diartikan
‘batu’ maka ute’ laggai (kepala desa) diterjemahkan sebagai ‘kepala batu’. Adalah ‘tidak sopan’ jika
menyebut kepala desa sebagai ‘kepala batu’ atau ‘kepala kemaluan’.
4
diperbincangkan kembali. Pertanyaannya, jika sudah ditolak, lalu mengapa nama laggai
menjadi perbincangan lagi dewasa ini?
B. Permasalahan
Penolakan dan penerimaan istilah laggai merupakan persoalan dalam melihat
perbedaan dan persamaan. Ada perbedaan-perbedaan yang dijadikan alasan penolakan untuk
menerima sesuatu yang dianggap milik liyan (the Other)9. Hal itu memunculkan tindak
pembedaan di satu sisi dan sekaligus tindak penyamaan di sisi lain, khususnya guna
mengklaim sesuatu. Mengapa pembedaan untuk mengklaim sesuatu sebagai milik 'kita'
semakin dikuatkan dan apakah yang melatar belakangi pentingnya makna kekitaan itu saat
ini bagi orang Mentawai? Persoalan penolakan orang Mentawai terhadap Perda No. 2 Tahun
2007 dan perdebatan nama untuk sistem pemerintahan terendah yang dianggap cocok untuk
Kabupaten Kepulauan Mentawai dijadikan sebagai pintu masuk untuk memahami lebih jauh
tentang persoalan wacana identitas atau ke-Mentawai-an itu sendiri. Secara lebih khusus
perhatian ditujukan pada wacana kekitaan dalam konteks penolakan laggai yang didasari
pada relasi oposisional ‘kami : mereka’.
Wacana kekitaan di Mentawai yang muncul terkait perbincangan laggai tidak terlepas
dari kekuatan eksternal dan internal yang ikut berperan, serta kaitannya dengan relasi
kekuasaan. Masing-masing orang akan memunculkan klaim kebenarannya sendiri-sendiri
dalam memaknai apa yang dianggap 'cocok' dan tidak sebagai milik 'kita' atau milik 'mereka'.
Lantas nama apa yang cocok untuk sistem administrasi pemerintahan terendah di Kabupaten
Kepulauan Mentawai, apakah laggai atau pulaggajat? Dalam perbincangan tersebut ada tarik
menarik antara orang Pagai-Sipora dan orang Siberut terkait nama pengganti desa di
Mentawai. Tarik menarik ini tidak hanya pada persoalan nama pengganti desa, namun lebih
jauh adalah persoalan wacana 'kekitaan', wacana yang dibangun tentang identitas atau ‘keMentawai-an’ dalam membedakan kelompok mereka dan kelompok lain (dianggap 'yang
Lain'). Berangkat dari gambaran tersebut, penelitian ini secara garis besar ingin menjawab
persoalan mengapa ada perbedaan makna ke-Mentawai-an dan mengapa perbedaan itu
semakin diperdebatkan dewasa ini. Ada beberapa hal menarik dan penting untuk dikaji
secara cermat di balik persoalan perdebatan makna ke-Mentawaian-an yang berlangsung
dewasa ini, yaitu:
9
Dalam tulisan ini istilah the Other, 'yang Lain', Liyan dan 'sang Liyan' digunakan secara bergantian untuk
merujuk hal yang sama yakni 'mereka' dan bukan 'kita'.
5
1. Bagaimana proses pembentukan wacana ke-Mentawai-an berlangsung dan kekuatankekuatan apa saja yang berperan dalam proses tersebut?
2. Bagaimana
hubungan
wacana
ke-Mentawai-an
dengan
perdebatan
sistem
administrasi pemerintahan terendah di Mentawai, khususnya terkait perdebatan nama
laggai ?
3. Bagaimana kesejajaran dan kesenjangan antara wacana ke-Mentawai-an dengan
praktik sosial budaya di Siberut?
C. Tujuan Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini difokuskan pada
persoalan wacana identitas di Mentawai melalui penolakan orang Siberut terhadap nama
laggai dan kaitannya dengan tuntutan sistem administrasi pemerintahan terendah di
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama ini, wacana-wacana orang kebanyakan dianggap
marjinal (dimarjinalkan) dan terkubur (dikubur) sehingga tidak diangkat ke publik. Melalui
studi ini wacana demikian tidak dikucilkan, justru wacana tersebut diberi tempat. Secara
teoritis kajian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pemikiran dan cara pandang
dalam melihat persoalan wacana identitas, terutama pada kelompok kesukuan (indigenous
people) di Indonesia, sekaligus makin memperkaya kemajemukan kebudayaan kita. Melalui
kajian ini dapat menghasilkan cara pandang yang lebih komprehensif dalam melihat
fenomena di Mentawai, khususnya yang berkenaan dengan wacana identitas dan diharapkan
kajian ini akan menjadi jembatan bagi penelitian-penelitian berikutnya agar dapat
memunculkan pemikiran yang lebih baru dan kritis tentang fenomena sosial budaya di
Mentawai.
Salah satu tantangan ke depan bagi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (nationstate) adalah tingkat diversitasnya yang tinggi yang dapat menjadi kekuatan positif, tetapi
sekaligus berpotensi konflik bila tidak dikelola dengan baik. Pemahaman tentang etnik lain
dapat menambah wawasan dan berguna bagi tumbuhnya sifat keterbukaan untuk menerima
berbagai perbedaan yang ada sebagai sebuah mozaik budaya di negeri ini. Untuk orang
Mentawai semoga lokalitas yang 'unik' menjadikan Mentawai menemukan identitas yang
inklusif. Di samping itu, dapat menambah pemahaman kita tentang identitas dalam kaitannya
dengan sistem administrasi pemerintahan terendah setempat (lokal), khususnya di daerah
yang identitas sukunya sangat beragam (bersuku-suku).
6
Subjektivitas masyarakat Mentawai menjadi hal penting dalam kajian ini. Tidak saja
untuk menunjukkan bagaimana keragaman ke-Mentawai-an itu dibangun, dimaknai dan
diperbincangkan oleh orang Mentawai sendiri, tetapi juga mengapa muncul pemaknaanpemaknaan yang berbeda. Selain itu, bagaimana perkembangan politik di luar Mentawai dan
isu-isu yang terkait dengan kemunculan pewacanaan identitas (ke-Mentawai-an) juga
menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pergulatan internal orang
Mentawai dalam mengurai persoalan yang dihadapi dapat digambarkan.
D. Tinjauan Pustaka
Sehubungan dengan tema kajian ini, tulisan yang menjadi kepustakaan dibagi atas tiga
tema. 1. Kebudayaan Mentawai: Identitas dalam Keunikan dan Keeksotikan. 2.
Pembangunan: Penyeragaman Identitas. 3. Kajian Identitas dan Globalisasi. Literatur
pertama untuk menunjukkan bagaimana wacana identitas Mentawai yang dibangun terkait
dengan pandangan orang luar (peneliti asing) tentang kebudayaan Mentawai yang unik dan
eksotik. Pandangan itu juga mempengaruhi peneliti-peneliti dari Indonesia, sehingga studi
yang dilakukan menekankan aspek-aspek budaya yang eksotik tersebut. Adapun yang kedua
merupakan hasil-hasil kajian yang melihat pengaruh luar (khususnya pembangunan)
terhadap kelompok etnik minoritas sebagai upaya penyeragaman identitas. Literatur ketiga
berkaitan dengan kajian Mentawai dengan konteks globalisasi. Ketiganya dianggap saling
terkait satu sama lain. Kemunculan wacana tentang identitas Mentawai merupakan bagian
dari wacana kolonial tentang masyarakat ‘primitif’ yang dalam perjalanannya wacana
tersebut kemudian diadopsi penguasa di era Orde Baru melalui wacana pembangunan.
Adapun wacana global tentang kelompok indigenous (masyarakat adat) ikut mempengaruhi
bagaimana kelompok etnik tertentu memaknai ulang identitas mereka dalam kaitannya
dengan interkoneksi global.
D. 1. Kebudayaan Mentawai: Identitas, “Keunikan dan Keeksotikan”
Untuk memahami konstruksi tentang ke-Mentawai-an, maka secara historis perlu
ditelusuri kembali sejak era kolonial sampai dengan Orde Baru. Konstruksi luar (orang
Barat) tentang orang Mentawai terbentuk karena para ilmuwan, penjelajah, pejabat dan
misionaris masa kolonial berperan membangun pandangan tentang orang Mentawai. Dari
tulisan mereka menunjukkan pandangan yang memberi label ‘primitif’ dan 'tidak beradab’
terhadap Mentawai. Representasi seperti itu muncul disebabkan karena orang Barat (Eropa
7
dan Amerika) memiliki sikap eurosentris yang memandang dan sekaligus menempatkan diri
mereka sebagai ‘orang-orang beradab’. Hal ini dapat dicermati, misalnya bagaimana
pandangan Maass (dalam Schefold, 1990; Eindhoven, 2002; Wagner, 2003) yang menyebut
Mentawai dengan nama “Liebenswűrdigen Wilden” yang berarti amiable (ramah-tamah) atau
obliging savages (orang liar yang penurut/patuh). Sebutan ‘amiable savage’ untuk Mentawai
tersebut banyak terinspirasi oleh kesan dari cara-cara hidup yang sederhana dan harmonis
serta penampilan mereka yang eksotik dengan cawat, hiasan bunga-bunga dan tato
(Schefold, 1998: 270-271). Penamaan amiable atau obliging savages kurang lebih sama
artinya dengan noble savage, orang 'biadab' yang terhormat atau orang 'biadab' yang agung.
Sekalipun sudah ada ‘basa basi’ dengan pemberian nama amiable atau nobel, mereka tetap
dicap savage. Pandangan savage inilah yang sebenarnya mendorong rasa ingin tahu orang
luar untuk datang ke Mentawai. Sudah tentu pandangan savage turut mendasari ide
pemberadaban orang Mentawai. Savage kadang diasosiasikan dengan 'keeksotikan'.
Pandangan tentang Mentawai sebagai kelompok etnik dengan adat dan tradisi yang berbeda
dari etnik mayoritas lain di Indonesia menjadikan Mentawai ‘unik’ dan ‘eksotik’. Keunikan
dan keeksotikan Mentawai menjadi daya tarik bagi para peneliti untuk mempelajarinya,
terutama kehidupan komunalnya. Misalnya, uma sebagai organisasi sosial politik dan
kekerabatan orang Mentawai Siberut menjadi perhatian dalam berbagai studi mereka tentang
Mentawai dalam relasinya dengan aspek-aspek kebudayaan yang dipilih (Loeb, 1928, 1929;
Schefold, 1974, 1985, 1988, 1991; Schefold dan Persoon, 1985; Coronese, 1986; Rudito,
1993, 1999, 2005; Rudito, dkk, 2003; Ermayanti, 1989; Roza, 1991, 1993, 1997, 2004;
Reeves, 2000).
Loeb (1928) dalam deskripsinya mengenai identitas Mentawai memberikan penekanan
pada uma, religi, dan organisasi sosial sebagai aspek penting yang saling terkait dalam
kehidupan orang Mentawai. Data-data hasil penelitiannya dilakukan di wilayah bagian
selatan Mentawai, yakni di Pagai yang dia sebut ‘Pageh’. Meskipun demikian, Loeb
menggunakan kategori Mentawai atau orang Mentawai untuk merujuk penghuni Pulau
‘Pageh’. Menurutnya, orang Mentawai di pulau itu melakukan banyak praktik ritual dalam
kehidupan kelompok uma (klen) dengan cara-cara pemujaan yang unik. Hal itu terutama
dikarenakan dalam pelaksanaan ritual uma melibatkan anggota-anggota uma dan pemimpin
ritual (sikerei). Para kerei merupakan tokoh penting dalam ritual yang dianggap memiliki
‘kekuatan magis’ (magical power) sehingga mampu berkomunikasi dengan alam
supranatural. Pengetahuan akan mantera yang mereka miliki, menjadikan sikerei mampu
menjembatani hubungan manusia dengan dunia supranatural. Selanjutnya Loeb (1929)
8
menunjukkan keterikatan yang kuat antara orang Mentawai dengan uma yang dilihat dari
efeknya terhadap keberlangsungan kesatuan tersebut sebagai pusat kehidupan yang
berpangkal pada religi asli mereka. Perhatian Loeb pada ritual uma yang dipraktikkan oleh
orang Mentawai dideskripsikannya melalui beragam punen.10
Keunikan kebudayaan Mentawai dalam praktik religi dan hubungannya dengan
kelompok uma pun banyak menyita perhatian Schefold (1974, 1985a, 1985b, 1988, 1991).
Kajian Schefold (1974) memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi di Mentawai,
terutama di bidang religi mereka. Deskripsinya mengenai identitas Mentawai dimulai dengan
pembahasan religi asli orang Mentawai, Arat Sabulungan. Dengan mengamati sistem
upacara ritual orang Mentawai Siberut, dia mencari penyebab terjadinya perubahanperubahan tersebut. Dia menyimpulkan, telah terjadi suatu perkembangan yang involutif
disebabkan oleh perubahan internal, terutama di bidang religi orang Mentawai dalam
kaitannya dengan kehidupan komunal uma.
Kajian Schefold yang lain (1985a) juga menempatkan uma sebagai hal penting dalam
melihat perubahan yang memuat tentang keseimbangan kehidupan orang Mentawai sebagai
salah satu suku-bangsa minoritas dan dunia modern yang mereka hadapi. Dia menunjukkan
bahwa orang Mentawai sedang dan telah dimasuki modernitas, khususnya konsumerisme.
Perubahan-perubahan yang terjadi melalui modernitas sejak kemerdekaan Indonesia
merupakan suatu serangan terhadap kebudayaan tradisional orang Mentawai. Menurut
Schefold, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.
Studinya ini menunjukkan sikap mempertentangkan modernitas dan tradisional, padahal
tradisi selalu berada dalam proses yang invented (Hobsbawn dan Ranger, 1993). Sikap
mempertentangkan itu muncul karena Schefold (1985a) menganggap Mentawai merupakan
salah satu kelompok yang terisolasi. Penulis tidak sepakat dengan anggapan ini, sebagaimana
dikatakan Reeves (2000) bahwa orang Mentawai telah lama melakukan kontak dengan orang
luar, bahkan sebelum era kolonial.
Pendeskripsian yang lebih padat mengenai kebudayaan Mentawai dapat ditemukan
dalam kajian lanjutan Schefold (1988). Di sini, identitas budaya Mentawai di Siberut
diperlihatkan Schefold melalui upacara ritual yang mengitari kehidupan orang Mentawai.
Menurutnya, berbagai upacara ritual dalam praktiknya tidak hanya memakan waktu yang
cukup lama, tetapi juga biaya yang cukup besar dengan melibatkan hampir keseluruhan
10
Punen tersebut antara lain adalah seperti punen membuka kampung, punen mendirikan bangunan uma,
punen untuk penatoan, punen untuk berburu monyet dan mengusir roh-roh jahat.
9
anggota uma. Pemaparannya yang deskriptif-interpretatif diperoleh melalui pengamatan yang
panjang dan seksama terhadap upacara puliaijat sebagai ritual utama kelompok suku (uma)
Sakuddei di Pulau Siberut. Schefold (1988) melihat upacara ritual itu berkaitan dengan
gagasan religi orang Mentawai Siberut yang berhubungan dengan jiwa dan roh manusia,
kekuatan impersonal, perantara, roh-roh nenek moyang, mitos dan juga berbagai macam tabu
yang harus dijalani. Oleh karena itu, praktik ritual uma menjadi hal penting dalam kehidupan
kelompok orang Mentawai di Siberut, meskipun masing-masing uma menyelenggarakan
ritual tersebut untuk kelompoknya sendiri. Hubungan orang Mentawai dengan religi mereka
adalah pertalian dengan kelompok uma mereka. Keberadaan uma dan pentingnya praktik
ritual uma masih menjadi fokus kajian Schefold (1991) yang dikembangkan dari kajiankajian sebelumnya. Dari studi itu dia memberikan penjelasan bahwa aktivitas religi, mata
pencaharian, simbol, budaya materi, dan teknik-teknik arsitektur rumah panggung (uma)
pada suku Sakuddei memiliki keterkaitan dengan praktik kehidupan komunal uma suku
tersebut.
Ahli lain yang juga tertarik dengan berbagai ritual dan kehidupan uma orang Mentawai
adalah Stefano Coronese11. Coronese (1986) memusatkan perhatiannya pada deskripsi religi
dan ritual suku yang disebutnya sebagai ‘kebudayaan asli’. Berbagai upacara ritual di
Mentawai yang digambarkannya menyangkut ritual siklus hidup (life-cycle), ritual yang
berhubungan dengan aktivitas mata pencaharian seperti membuat ladang baru, dan ritual
perdamaian (Coronese, 1986). Kajiannya diperkaya dengan telaah historis tentang
kedatangan Sasareu, seperti: pegawai kolonial, misionaris, ilmuwan dan para pedagang yang
menunjukkan relasi orang Mentawai dengan Sasareu. Relasi itu telah berlangsung lama di
Mentawai, setidaknya sejak abad ke-17.
Relasi orang Mentawai dengan Sasareu ini tidak dapat dilepaskan dari wacana
pembangunan yang memperlihatkan kuatnya intervensi negara terhadap kehidupan uma dan
praktik di dalamnya. Kasus ini dapat kita temukan antara lain dalam studi Schefold (1985b),
Persoon dan Schefold, (1985), Wagner (1985), Coronese (1986), Roza (1991) dan Zakaria
(1996). Kajian mereka menyoroti perihal pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek
kebudayaan Mentawai dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, agar orang
Mentawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkaitan dengan implementasi
program pembangunan di sana. Para peneliti tersebut beranggapan, perubahan yang
11
Seorang pastor dari Italia. Sebagai seorang pastor tentu saja sangat beralasan jika keunikan Mentawai dalam
berbagai ritual yang animistik menjadi perhatian utama bagi Coronese (1986). Alasan inilah yang
mendorongnya untuk memainkan peran yang penting sebagai penyiar agama.
10
disebabkan oleh modernisasi menimbulkan kesulitan bagi orang Mentawai untuk
menyesuaikan nilai-nilai setempat dengan kehidupan modern. Selain itu, pembangunan yang
dilakukan dengan menyeragamkan alasan untuk semua tempat di negara ini, menunjukkan
kuatnya politik penataan etnik dari para pemegang kekuasaan.
Kajian lain yang terkait dengan keberadaan uma sebagai kumpulan orang yang
berkerabat menurut garis patrilineal dalam kehidupan orang Mentawai Siberut juga menjadi
perhatian Ermayanti (1989). Dia mengkaji fungsi kerei bagi masyarakat Mentawai di Siberut
Selatan, khususnya di Lembah Rereiket. Fungsi kerei dilihat dari peranannya yang sangat
penting dalam berbagai ritual, tidak hanya dalam ritual penyembuhan tetapi juga dalam
berbagai ritual klen (uma)12. Kerei menjadi pemimpin dalam pelaksanaan berbagai ritual
uma, karena kemampuannya sebagai perantara dunia manusia dan alam roh. Dengan
demikian, kerei juga menjadi penanda yang unik bagi ke-Mentawai-an.
Kehidupan orang Mentawai Siberut yang terpusat pada uma juga berlangsung di Desa
Matotonan (Roza, 1997). Dia tertarik pada fungsi uma dalam menjaga keseimbangan
kehidupan masyarakat Mentawai. Menurutnya, kehidupan komunal uma masih penting bagi
orang Mentawai Siberut, khususnya di Matotonan. Dalam penelitian lanjutannya, menurut
Roza (2004) penerapan denda adat (tulou) sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang
muncul di tengah masyarakat juga tidak terlepas dari kehidupan kelompok uma. Dalam
tulisannya itu Roza (2004) tidak mencoba melihat masalah tulou ini dalam kaitannya dengan
intervensi pihak luar (Sasareu), khususnya pemerintah, karena tulou ini pernah ditetapkan
pemerintah menjadi peraturan desa (lihat Delfi, 2005). Tentunya akan lebih menarik jika
respons dari masyarakat Mentawai terhadap intervensi Sasareu yang menformalisasi aturan
adat tersebut juga dibahas sehingga subjektivitas orang Mentawai dengan kehidupan yang
terpusat pada uma tidak diabaikan.
Perhatian pada kehidupan uma dan praktik ritualnya oleh Rudito, dkk (2002) dibahas
dalam keterkaitannya dengan praktik perburuan dan pola konsumsi orang Mentawai di
Siberut Selatan. Praktik perburuan itu tidak hanya menjadi kegiatan dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan protein hewani saja, tetapi lebih diutamakan sebagai bagian dari
kegiatan ritual Arat Sabulungan di Siberut. Hal itu ditunjukkan melalui aktivitas perburuan
untuk mengakhiri atau menutup kegiatan ritual uma. Sayangnya, kajian ini melupakan
12
Tema yang sama juga bisa ditemukan dalam Roza (1993). Kedua kajian tersebut dilakukan di lokasi yang
sama, yakni di desa Matotonan, Siberut Selatan. Membandingkan dua kajian tersebut, kajian Ermayanti
(1989) melihat peranan kerei secara lebih luas dalam kehidupan uma, tidak hanya dalam aspek pengobatan
tradisional seperti yang dilakukan Roza (1993).
11
pembahasan perihal pertentangan antara wacana perlindungan binatang-binatang buruan
(primata endemik) dari kepunahan dengan kepentingan aktivitas berburu sebagai bagian dari
praktik ritual uma bagi masyarakat Mentawai di Siberut. Hal tersebut menarik, karena pihak
pemerintah (penguasa) telah menjadikan sebagian besar wilayah perburuan di Siberut
sebagai kawasan Taman Nasional Siberut (TNS). Konservasi hewan ini jelas bertentangan
dengan kepentingan aktivitas perburuan kolektif yang menjadi bagian dari praktik ritual
masyarakat setempat.
Kajian lain yang berkaitan dengan persoalan era otonomi daerah dilakukan Rudito,
dkk. (2004) perlu diberi perhatian. Penelitian ini membahas tentang konsep kewilayahan dan
sistem pemerintahan menurut kebudayaan Mentawai. Menurut mereka, pulaggajat13
merupakan nama yang paling cocok digunakan di Mentawai, karena pulaggajat merupakan
gabungan dari beberapa laggai. Oleh karena itu, desa di Mentawai dapat diganti dengan
pulaggajat. Konsep pulaggajat tidak sama dengan laggai seperti yang diusulkan dalam
rancangan peraturan daerah, dan secara historis keduanya belum pernah berlaku sebagai
pranata politis di Siberut. Selain itu, mereka tidak mempertanyakan mengapa model
pemerintahan laggai ditolak oleh orang Mentawai di Siberut. Dalam studi ini, perhatian tidak
lagi difokuskan pada alasan penolakan semata, tetapi lebih pada persoalan mengapa
perbedaan makna itu menjadi penting di Mentawai saat ini (politik pembedaan) dalam
kaitannya dengan identitas.
Pulaggajat sebenarnya bukan merupakan pranata politis yang menyatukan semua uma
(klen) yang tersebar di wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan tidak adanya pranata politis
yang dapat menyatukan seluruh uma yang terdapat di lembah (Schefold, 1991: 121). Oleh
karena itu, tidak ada orang yang menjadi ‘kepala pulaggajat’ di masing-masing lembah.
Masing-masing uma berhak sepenuhnya mengurus sendiri hubungan mereka dengan uma
lain. Alasan ini yang menyebabkan uma (klen) dalam kehidupan orang Mentawai Siberut
sangat penting. Terkait dengan pranata ini, Rudito (2005) berpandangan bahwa pranata yang
mencakup keseluruhan aturan hidup orang Mentawai dapat ditemui dalam upacara bebeitei
uma. Melalui upacara ini dia memahami keterkaitan pengetahuan dan sistem keyakinan
13
Rudito dkk, (2004) menyebut konsep kewilayahan tersebut dengan pulagajat, tetapi menurut hemat penulis
orang Mentawai menyebutnya dengan pulaggajat atau pulaggaijat. Baik pulaggajat atau pun laggai ini
sebagai pranata politis belum pernah berlaku di Mentawai (lihat Delfi, 2005). Meskipun demikian, ketika
menanyakan dari kampung mana seseorang berasal biasanya Orang Mentawai di Siberut mengatakan, “kaipa
pulaggajatnu?”, sementara orang Mentawai di Sipora dan Pagai biasanya mengatakan, “kaipa laggainu?”.
Lihat juga Coronese dalam tulisannya tentang penyadaran etnik Mentawai (1985:102) mengemukakan
bahwa kampung atau pulaggajat bagi orang Mentawai tidak sama dengan kampung yang biasa dipahami
oleh orang luar.
12
orang Mentawai terhadap alam gaib yang melingkupi kehidupan dalam komunitas mereka.
Menurutnya, nilai budaya inti ini dipakai sebagai dasar pedoman bagi tindakan-tindakan
dalam memahami dan menginterpretasi lingkungan yang mereka wujudkan dalam pranata
sosial tersendiri, yaitu upacara bebeitei uma. Kajiannya ini selain melihat kebudayaan
Mentawai secara fungsional juga memperlihatkan penguatan lokalitas orang Mentawai yang
meningkat setelah menjadi daerah otonom.
Dari literatur-literatur yang telah disebutkan di atas, tampaknya uma telah menjadi
salah satu penanda penting bagi ke-Mentawai-an seseorang. Kajian-kajian tersebut penting
untuk dipelajari lagi, karena memberikan beragam deskripsi tentang masyarakat dan
kebudayaan Mentawai yang dipandang ‘unik’ dari aspek-aspek yang berbeda. Hal ini sangat
membantu peneliti memunculkan tema lain, sehingga tidak melakukan penelitian yang
bersifat pengulangan. Perlu dicermati bahwa kajian-kajian yang digambarkan di atas belum
dipahami dari cara bagaimana kebudayaan tersebut diproduksi dan dikonstruksi di dalam
wacana oleh orang Mentawai.
D. 2. Pembangunan: Penyeragaman Identitas
Gagasan pembangunan yang diwacanakan banyak negara maju muncul dari
perkembangan sejarah peradaban mereka dan diyakini menjadi kunci kemajuan. Cara
pandang tersebut mengakibatkan mereka menilai pandangan dan praktik hidup negara
berkembang tidak sesuai dengan gagasan kemajuan yang diciptakan negara maju. Hal ini
mendorong negara maju untuk mengubah cara pandang masyarakat di luar mereka dengan
meyebarkan ide-ide modernisme melalui wacana pembangunan. Di Indonesia, beberapa
kajian dilakukan untuk memahami hubungan wacana pembangunan dengan keinginan untuk
mengubah pandangan dan praktik hidup kelompok etnik minoritas dan perubahan yang
dialami terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Pemahaman kajian ini dimaksudkan
untuk membuka wawasan mengenai apa yang dialami suku minoritas lainnya di Indonesia
juga terjadi di Mentawai. Kajian-kajian tersebut lebih banyak memperlihatkan pertentangan
modernisasi (pembangunan) dengan nilai-nilai lokal (tradisi) etnik minoritas di Indonesia.
Misalnya, serangan terhadap agama lokal (indigenous) dengan mengatasnamakan
pembangunan, sehingga proses marjinalisasi terhadap suku minoritas dan juga hegemoni
agama resmi yang sesungguhnya merupakan ‘agama impor’14 (berasal dari luar negeri),
dapat berlangsung di sana. Pandangan main-stream mengenai kelompok kesukuan yang
14
Agama yang bukan indigenous tetapi berasal dari luar dianggap universal religions.
13
‘terbelakang’ dan ‘tidak berbudaya’ mengakibatkan mereka harus dibangun, diagamakan
dan dimaksudkan untuk membuat yang lain menjadi seragam. Hal semacam ini dapat
ditemukan dalam penelitian Djuweng (1996); Atkinson (1985); Schefold (1985); Zakaria
(1996); Giay (1996); Beanal (1997); dan Schoorl (1997).
Kajian mengenai suku minoritas, selain menekankan pada hegemoni agama resmi, juga
melihat proses marjinalisasi yang terjadi karena pengambilalihan tanah mereka. Negara
dengan Undang-undang Agrarianya telah mengklaim tanah-tanah milik suku atau kelompok
masyarakat adat sebagai milik negara. Ini mengakibatkan hilangnya penguasaan hak tanah
yang sebelumnya diakui menurut hukum adat setempat. Ditambah lagi keterbatasan yang
dimiliki suku minoritas untuk bersaing dalam memperebutkan peluang ekonomi. Kompetisi
dengan para pendatang yang memiliki kemampuan bersaing lebih membuat kelompok etnik
lokal termarjinalkan. Gambaran kondisi demikian dapat dicermati dalam kajian-kajian Giay
(1996); Beanal (1997); van den Broek (1998); Tirtosudarmo (2002); dan Ngadisah (2003).
Kajian-kajian demikian penting untuk memahami bagaimana hegemoni telah memarjinalkan
etnik-etnik kecil di negeri ini, namun studi demikian terlalu mempertentangkan suku-suku
minoritas dengan modernitas (pembangunan). Kelemahan lain dari kajian tersebut yakni
memandang masyarakat kesukuan sebagai subjek pasif yang seolah-olah menerima dan
mengikuti saja keinginan dari berbagai pihak penguasa (orang luar) dalam menentukan
identitas kesukuan dan pilihan hidup mereka. Padahal, masyarakat kelompok kesukuan juga
memiliki kekuatan untuk tidak hanya menerima hal tersebut, melainkan juga berperan aktif
dalam membentuk wacana identitas mereka. Tidak hanya itu, proses pembentukan wacana
identitas juga terjadi melalui pertentangan-pertentangan dan negosiasi di dalam masyarakat
itu sendiri.
D. 3. Kajian Identitas dan Globalisasi
Studi tentang identitas Mentawai yang cukup berbeda dari yang dilakukan peneliti lain
sebelumnya adalah studinya Reeves (1999; 2000). Kajiannya mengenai produksi sosial dari
ruang dan kekerabatan orang Mentawai di Madobag, dihubungkan dengan praktik-praktik
sosial. Artinya, keberadaan uma ditentukan oleh praktik sosial di dalamnya. Reeves (1999)
melihat identitas orang Mentawai di Madobag yang merupakan pemukiman relokasi dan
dihuni oleh orang Mentawai yang relatif sama, karena memiliki kesamaan lembah asal,
sehingga identitas Sarereiket (orang-orang yang berasal dari Lembah Rereiket) lebih dapat
ditonjolkan. Meskipun Reeves (2000) menekankan pada subjektivitas orang Mentawai
14
Madobag, tetapi kajiannya belum membahas bagaimana identitas Sarereiket tersebut
dibangun dalam relasinya dengan kelompok yang berasal dari lembah yang lain, misalnya
hubungan antara orang Rereiket dengan orang Sabirut. Apalagi dalam relasinya dengan
orang-orang dari pulau lain di selatan yang disebut orang Sakalagan, serta Sasareu.
Selanjutnya, kajian Persoon (2002) dan Eindhoven (2002; 2007) juga berbeda dari
kajian-kajian Mentawai sebelumnya. Mereka menyoroti masalah globalisasi dan kebudayaan
lokal (Mentawai) sebagai kelompok minoritas yang selama ini dianggap ‘terisolasi’. Menurut
mereka, hubungan antara wacana internasional, nasional dan lokal berdampak pada gerakan
masyarakat adat di Mentawai. Hal ini ditunjukkan dengan bangkitnya solidaritas identitas
orang Mentawai dengan munculnya kelompok elit terpelajar yang mulai kritis terhadap
kebijakan pemerintah mengenai persoalan kebudayaan mereka.
Melalui kajian itu, dapat diketahui bahwa kelompok terpelajar Mentawai menggalang
kekuatan untuk melawan kelompok dominan (Minangkabau) yang dinilai selama ini telah
mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Sifat kritis kaum terpelajar ini juga
dimungkinkan oleh arus demokratisasi dan grass-root globalization15, serta perhatian
internasional terhadap masyarakat asli (indigenous people). Hanya saja kajian tersebut
memfokuskan perhatian pada kelompok elit terpelajar dan bukan pada orang Mentawai
kebanyakan serta elit sosial budaya, sedangkan perdebatan wacana identitas tidak hanya
berlangsung di antara kelompok elit terpelajar saja. Selain itu, baik Persoon (2002); maupun
Eindhoven (2002; 2007) dan juga Reeves (2000) dalam kajian mereka tentang identitas
Mentawai tampak mengabaikan wacana kaum perempuannya. Kurangnya perhatian terhadap
pandangan dan keterlibatan kaum perempuan ini lah yang juga coba diisi dan sekaligus
membedakannya dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.
Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan cara pengonstruksian identitas
melalui wacana tulis (media) dengan wacana lisan yang muncul dalam perbincangan seharihari orang Mentawai. Perdebatan-perdebatan di antara orang Mentawai dalam mengonstruksi
makna identitas mereka melalui wacana kebudayaan dan relasinya dengan kepentingan dan
kekuasaan menurut hemat pengetahuan penulis belum dilakukan. Selain itu, studi-studi yang
sudah dilakukan terdahulu belum menilik problem internal di kalangan orang Mentawai
sendiri terkait persoalan identitas yang dihadapi.
15
Grass-root globalization atau globalisasi dari bawah.
15
E. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori
E. 1 . Kerangka Konseptual
E. 1. 1. Konstruksi Identitas dan Etnisitas
Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi sarat oleh berbagai
kepentingan (Berger dan Luckmann, 1990). Konstruksi sosial merupakan gagasan yang
senantiasa hadir dalam kajian atau perbincangan mengenai realitas sosial. Menurut Turner,
dkk. (dalam Afif, 2012: 19) realitas sosial merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai yang
menjadi acuan bagi identitas kelompok yang kemudian melahirkan batas-batas
antarkelompok dalam perkembangannya. Demikian juga halnya dengan identitas etnik.
Dalam pandangan Barth (1983) identitas (etnik) merupakan hasil dari proses sosial yang
kompleks, dimana batasan-batasan simbolik terus menerus membangun dan dibangun
melalui mitologi, sejarah, bahasa maupun pengalaman masa lalu. Batasan simbolik penting
sebagai pembeda sebagaimana dikemukakan De Vos (1982: 16) bahwa identitas etnik dari
sekelompok orang terdiri dari simbol subjektif atau dengan penggunaan hal yang emblematic
dari aspek-aspek kultural untuk membedakan diri dari kelompok lainnya.
Identitas budaya yang terus dibangun itu menjadi suatu konstruksi yang
memungkinkan untuk digunakan dalam memperkuat identitas-identitas tertentu, terutama
pada saat suatu kelompok sedang menghadapi suatu ancaman (Maunati, 2004: 37). Perasaan
terancam mengakibatkan identitas sering ditunjukkan sebagai hal yang bertentangan atau
sengaja dipertentangkan terhadap kelompok tertentu di luar mereka. Contohnya orang Bali,
mereka mengidentifikasi dirinya dengan menyebutkan sebuah identitas yang beroposisi
dengan Islam sebagai kelompok dominan (Picard dalam Maunati, 2004: 27).
Mempertentangkan suatu identitas dengan identitas lain di luarnya, seringkali
dilakukan kelompok minoritas/marjinal terhadap kelompok dominan. Hal itu menjadikan
perbedaan-perbedaan sebagai penanda identitas itu semakin terlihat. Dalam proses konstruksi
identitas, faktor historis dan kepentingan-kepentingan subjektif dari para aktor berperan
penting. Dengan demikian, pertentangan yang didasari oleh penekanan pada perbedaan itu
menunjukkan wacana politik identitas semakin menguat di era Otonomi Daerah. Salah satu
pertentangan itu, misalnya antara Mentawai dan Minangkabau berkenaan dengan sistem
pemerintahan terendah. Perbedaan etnik antara ‘mereka’ (Mentawai) dengan etnik di luarnya
(misalnya Minangkabau) merupakan bagian dari upaya-upaya politis yang memicu elit
Mentawai menciptakan nama laggai.
16
Adapun etnisitas, muncul di sini sebagai hasil dari proses hubungan antaretnik yang
telah lama terjalin. Etnisitas juga mengandung dimensi politik dan juga terkait dengan
ideologi dan kepentingan tertentu dalam satu negara yang multietnis (Allahar, 2005) seperti
di negara kita. Menurut Barker (2005: 27) etnisitas merupakan konsep kultural yang terpusat
pada norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik yang menandai proses pembentukan
batas kultural. Batas-batas kultural yang dibentuk berdasarkan aspek-aspek kultural dilihat
dalam kerangka relasi antaretnik. Relasi yang dibangun dengan sejumlah others akan
memberikan pengetahuan tentang others. Bagi orang Mentawai, hubungan antaretnik itu
telah memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai etnik lainnya, terutama etnik
Minangkabau.
Kelompok etnik tidaklah sama dengan bangsa, karena konsep bangsa mempunyai
hubungan langsung dengan suatu negara modern (Eriksen, 1993: 99). Etnik merupakan salah
satu kategori sosial, sementara identitas dibentuk berdasarkan keanggotaan dari kategori
sosial yang ada. Melalui identitas kelompok atau identitas sosial, individu akan terkait
dengan kelompoknya (in-group) 16. Keanggotaan kelompok dapat mempengaruhi
keyakinan individu, sikap, dan perilaku dalam hubungan mereka dengan anggota
kelompok sosial lainnya (out-group) 17. Menurut Rex (dalam Abdillah, 2002: 15),
konsep etnik ini menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok atau
individu-individu yang menyatukan diri dalam kolektivitas. Dengan sense of collectiveness
ini, anggota dalam kelompok etnik akan memunculkan kesadaran untuk mengidentifikasi diri
mereka ke dalam kelompok etnik tertentu. Kesadaran demikian pada akhirnya memunculkan
gagasan pembedaan dari masing-masing etnik, baik mengenai klaim asal-usul maupun
karakteristik budaya, sehingga pembedaan batas-batas kultural menjadi jelas.
Berkaitan dengan identifikasi kelompok etnik tersebut, ada dua pandangan yang
diajukan oleh Manger (dalam Abdillah, 2002: 15), yaitu: 1) sebagai sebuah unit objektif
yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang; dan 2) hanya sekadar produk
pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya sebagai suatu kelompok etnik tertentu.
Sebagai hasil dari proses hubungan, etnisitas menjadi aspek penting dalam hubungan16
17
Ingroup menjadikan individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu akan menempatkan nilainilai yang berkembang dalam kelompoknya sebagai rujukan dan bagian dari identitas sosialnya, sementara
bersikap sebaliknya untuk kelompok lain dan cenderung merendahkan nilai-nilai yang dianut kelompok lain
(outgroup) (Krizan dan Baron dalam Afif, 2012: 19).
Outgroup merupakan kategori sosial atau kelompok di mana individu tidak merasa menjadi bagian dari
kategori sosial tertentu sehingga menimbulkan rasa tidak suka, menghindar, membandingkan dan
berkompetisi, bahkan dapat melahirkan konflik dengan kelompok lain (Direnzo dalam Afif, 2012: 20).
17
hubungan politik yang terjalin di antara orang Mentawai dan orang luar. Hasil dari proses
hubungan yang dibangun antaretnik menjadikan setiap kelompok berusaha mendefinisikan
identitas etnik mereka. Menurut Wallerstein (dalam Kaufert, 1977: 127) identitas etnik
dimaknai sebagai suatu produk dari self-definition dari anggota kelompok (in-group) dan
juga definisi yang diterima dari anggota kelompok lain di luar (out-group). Adapun praktik
aktual dari etnisitas ini ditentukan oleh posisi relatif dari kekuasaan (Lewellen, 2002: 112)
yang terbentuk melalui relasi antarkelompok yang ada. Tidak hanya itu etnisitas juga
menandai relasi marjinalitas, pusat dan pinggiran, dalam konteks perubahan bentuk dan
sejarah (Barker, 2005). Etnik minoritas seperti Mentawai, berusaha melakukan kontrol atas
identitas mereka untuk mendefinisikan diri dengan cara-cara mereka sendiri. Mendefinisikan
diri dalam istilah-istilah positif merupakan hal yang mungkin paling penting dilakukan
(Ritzer, 2003), bahkan dalam etnik yang sama. Ini dikarenakan individu cenderung memberi
evaluasi positif terhadap kelompok sendiri dari pada untuk kelompok lain yang dalam teori
kategorisasi, proses tersebut disebut stereotyping dan self-stereotyping (Hogg dkk, dalam
Afif, 2012: 27). Hal itu menunjukkan bahwa usaha atau cara-cara yang dilakukan tersebut
bersifat selektif.
Peran aktor sangat penting dalam menyeleksi, memproduksi makna, dan sekaligus
menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial. Kemudian dengan bekal serangkaian pola
yang diinternalisasikan itu subjek menggunakannya untuk memaknai dunia sosialnya
(Bourdieu, 1994) yang senantiasa berubah. Ini dimungkinkan karena setiap manusia
merupakan agen-agen aktif dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Maksudnya,
semua aktor sosial banyak mengetahui kondisi-kondisi dan bermacam konsekuensi atas apa
yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditekankan Giddens (2003:
347) bahwa aktor terus berusaha mengetahui apa yang terjadi dalam aktivitas keseharian
kehidupan sosial mereka dan agen berarti karena ada kekuasaan, yang dengan adanya
tindakan akan dapat mengubah situasi.
Keterkaitan identitas dengan kekuasaan juga menjadi perhatian ahli lain. Misalnya
menurut Stuart Hall (dalam Barker, 2005), identitas menjadi subjek dari permainan sejarah18,
18
Sehubungan dengan ikutnya sejarah dalam membentuk identitas masyarakat pendukungnya dapat kita
pahami, orang-orang di Asia Tenggara dalam sejarahnya mendapat dua pengaruh kebudayaan besar yaitu
India dan Cina. Pengaruh tersebut telah mewarnai kebudayaan masyarakat di kawasan tersebut dan
mempengaruhi sejarah pembentukan identitas mereka. Komunitas Cina di kota-kota pesisir Jawa misalnya,
mereka tinggal di perkampungan khusus yang lazim disebut pecinan telah membentuk komunitas sendiri
dengan identitas pecinannya. Sekalipun mereka telah berusaha untuk membaurkan diri dengan kebudayaan
Jawa (Lohanda, 1994:57), namun mereka tampil dengan identitas pecinannya. Jadi, agama, latar belakang
18
kebudayaan, dan kekuasaan secara terus menerus. Identitas berubah menurut bagaimana
subjek ditunjuk, direpresentasikan, dan dibangun oleh identitas yang beragam dan terpecahpecah (Barker, 2005). Oleh karena itu, identitas bukanlah suatu yang tunggal dan tetap.
Identitas dibentuk berdasarkan aspek kebudayaan yang berhubungan langsung dengan proses
pembentukan identitas itu sendiri sebagai suatu yang dikonstruksi (Berger dan Luckmann,
1990; Eriksen, 1993; Kipp, 1993; Sarup, 1999; Piliang, 2002; Hall dalam Barker, 2005).
Oleh karenanya identitas selalu memberikan ruang yang terus menerus dapat ditafsirkan
sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok dalam kehidupannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, identitas mungkin mengacu pada keunikan individu
sebagai suatu kelompok sosial (Eriksen, 1993: 156). Menurut Hall (dalam Barker, 2005)
identitas itu terdiri dari identitas diri dan identitas sosial. Identitas tentang diri dan sosial
tersebut merupakan konsep tentang diri kita dan tentang relasi kita dengan orang lain sebagai
suatu proses menjadi. Oleh karena itu identitas sosial merupakan persoalan kategorisasi diri
yang ditandai proses pengendalian lingkungan dengan cara mengelompokkan objek-objek ke
dalam satuan sosial tertentu, sehingga proses identifikasi diri dan kelompok dapat
berlangsung lebih mudah (Brewer dalam Afif, 2012: 37). Giddens (2003) berpendapat,
identitas merupakan cara berpikir tentang kita. Hanya saja, pikiran tentang diri kita dapat
berubah dari satu situasi ke situasi yang lain menurut ruang dan waktunya. Oleh karena itu,
identitas bersifat situasional (Nagata, 1974; Kaufert, 1977; Eriksen, 1993; Picard dalam
Maunati, 2004). Sejalan dengan pendapat yang berhubungan dengan cara berfikir tentang
kekitaan yang situasional dan dinamis tersebut, sebagaimana yang disebutkan Barker (2005:
171), identitas merupakan konstruksi diskursif yang maknanya dapat berubah menurut ruang,
waktu, dan pemakaian. Artinya, makna yang dibangun dipengaruhi oleh berbagai hal yang
terjadi di masyarakat dan makna akan selalu berhubungan dengan realitas sosial dan
kekuasaan.
Makna tidak hanya sesuatu yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya,
melainkan dipengaruhi dan dibentuk oleh manusia secara aktif dalam konteks sosial yang
mengandung kekuasaan. Pemahaman terhadap proses konstruksi makna menjadi hal yang
pokok dalam studi ini, karena persoalan identitas juga menyangkut pemaknaan yang
berkaitan dengan pelabelan, pengkategorian dan pengidentifikasian. Orang Mentawai
sebagai individu atau kelompok cenderung membuat pengkategorian dunia sosial secara
etnik, sejarah dan lingkungan geografis dapat memberi kekhasan yang menjadi penanda identitas budaya
pada kelompok tertentu.
19
tegas, seperti ‘kita’ dan ‘mereka’. Dalam relasi sosial pengidentifikasian di sini sebenarnya
berkaitan dengan cara memandang hubungan ‘kita’ dan ‘mereka’, tidak hanya dalam relasi
etnik yang berbeda tetapi juga relasi di dalam etnik yang sama. Dengan demikian, identitas
berkaitan dengan penafsiran-penafsiran terhadap 'yang Lain'.
Sehubungan dengan hal tersebut menurut Eriksen (1993: 117), identitas etnik dibangun
sesuai dengan situasi yang ada dan disusun dalam hubungannya dengan sejumlah others.
Dalam relasi dengan kelompok lain (other), penguatan dan peneguhan identitas akan
muncul, karena pengelompokan ‘kita’ dan yang ‘bukan kita’ selalu hadir melalui relasi-relasi
yang dibangun. Di Mentawai misalnya, ada kata Simattawai (orang Mentawai) dan Sasareu
(orang luar) yang menunjukkan pengelompokan seperti itu (Delfi, 2005)19. Binary opposition
demikian juga tampak dari pengelompokan untuk orang Mentawai di selatan yang disebut
Sakalagan dan orang di bagian utara menyebut kelompok mereka Sakalelegat. Sejalan
dengan yang dikemukakan oleh Calhoun (1994) dan Castells (2000), pembedaan ‘kita’ dan
‘mereka’ ada dalam semua kebudayaan. Prinsip ini yang kemudian mendasari praktik
eksklusi dan inklusi. Melalui pembedaan itu pula maka dikotomi-dikotomi, pertentangan dan
diskriminasi juga ada (sengaja dibuat) antara ‘kita’ dan ‘mereka’, karena dunia sosial sudah
dikategorikan secara berbeda.
Cara orang untuk melihat identitas-identitas kultural sebagai konstruksi sedemikian
pun merupakan cara yang mungkin digunakan untuk memperkuat identitas pada saat suatu
kelompok sedang menghadapi ancaman dari luar (Eriksen, 1993; Maunati, 2004), termasuk
ancaman budaya kelompok dominan, maupun ancaman global. Pembedaan tersebut semakin
dipertegas dengan usaha mereka-ulang identitas atau bahkan juga menciptakannya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1990: 323), dampak kuat dari pasar global
melalui komodifikasi kebudayaan bukannya melahirkan keseragaman, tetapi justru
sebaliknya memunculkan identitas kultural yang direka-ulang dalam interaksi antara yang
global dan yang lokal. Seringkali suatu yang dikatakan lokal oleh kelompok tertentu, boleh
jadi merupakan hasil proses reka-ulang yang kemudian dengan sengaja ditonjol-tonjolkan
sehingga seolah-olah sifatnya ‘partikularistik’.
Lokalitas selalu muncul dari praktik-praktik subjek lokal dalam lingkungan sekitarnya
yang spesifik dan subjek-subjek lokal tersebut terlibat dalam aktivitas sosial dari produksi,
19
Bagi orang Minangkabau juga ada pengelompokkan ‘urang awak’ dan yang ‘bukan urang awak’, dan bagi
orang Batak juga ada ‘halak kita’ dan yang ‘bukan halak kita’ yang menunjukkan bahwa masing-masing
etnik membedakan diri mereka dengan etnik lain di luarnya.
20
representasi, dan reproduksi (Appadurai, 2005: 195-198). Perlu diketahui, subjek-subjek
lokal ini bukanlah individu-individu, melainkan aktor sosial kolektif melalui mana individuindividu memberi makna holistis dari pengalaman-pengalaman mereka (Castells, 2000: 10).
Produksi lokalitas yang dilakukan aktor sosial erat terkait dengan media dan teknologi
komunikasi global. Jika ada masalah muncul dan menjadi perhatian yang dominan, misalnya
gagasan nasionalisme dan nation-state, demokrasi, human rights (indigenous rights) menjadi
bagian dari persoalan global, maka produksi lokalitas menjadi sesuatu yang bersifat global
(Appadurai, 2005). Jadi perubahan-perubahan di tingkat lokal, nasional dan internasional
(global) dapat mempengaruhi produksi lokalitas di berbagai tempat, tidak terkecuali di
Mentawai.
Interaksi antara yang lokal, nasional dan global dalam produksi lokalitas akan
memunculkan sesuatu yang dipandang ‘khas’ (partikularistik) dan kemudian dijadikan
sesuatu yang dapat diklaim sebagai milik ‘kita’ dan bukannya milik ‘orang lain’. Sőkefeld
(2001) menyebutkan bahwa identitas berarti juga suatu klaim. Klaim-klaim tersebut terkait
dengan cara-cara pengelompokan yang melibatkan tindak eksklusi dan inklusi yang
didasarkan pada konsep kesamaan dan perbedaan (Simatupang, 2006: 78). Umumnya ke
dalam kelompok sendiri orang berupaya melakukan tindak penyamaan dan ke luar
kelompoknya melakukan tindak pembedaan. Pengelompokan ‘kita’ dan ‘mereka’ dapat
dipengaruhi dan ditentukan juga oleh kesamaan daerah asal, kelompok etnik dan agama.
Agama yang dianut oleh ‘kita’ dan yang dianut oleh others bahkan mampu
memisahkan orang-orang yang satu etnik sekalipun. Banyak orang (menjadi) Melayu yang
dikenal sekarang di Kalimantan, termasuk orang Kutai dulunya juga dianggap orang Dayak
(Maunati, 2004:61). Mayoritas orang Melayu di Kalimantan pada dasarnya pun merupakan
orang Dayak yang kemudian masuk Islam (Avé dan King dalam Maunati, 2004:61-62). Hal
yang sama juga terjadi pada orang Batak Karo yang mengubah identitas etnik Karonya
menjadi Melayu setelah mereka masuk Islam (Kipp, 1999). Agama menyebabkan sebagian
orang menjadi other di dalam kelompok etniknya sendiri dan sebaliknya juga bisa
menjadikan sebagian orang di luar kelompok etniknya yang semula other menjadi ‘kita’. Hal
demikian menunjukkan bahwa identitas dapat terus berlangsung karena agama dan begitu
juga sebaliknya (Babcock, 1989). Adapun penanda identitas budaya bisa saja berasal dari
21
suatu kekhasan yang terdapat pada praktik-praktik keagamaan dari kelompok tertentu 20 yang
sangat mungkin pula mengalami berbagai perubahan.
Perubahan-perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari politik permainan identitas yang
dimanifestasikan dalam bermacam aktivitas pada ruang dan waktu tertentu. Sebagai sesuatu
yang setiap saat dapat berubah, konsep identitas bisa dipandang sebagai usaha yang tiada
akhir dan terus berkelanjutan. Dengan demikian, identitas bukan merupakan sesuatu yang
final, statis dan succeed, melainkan sesuatu yang tidak pernah sempurna (Hall dalam Barker,
2005). Sebagai sesuatu yang tidak sempurna, identitas memerlukan media untuk terus
tumbuh dan berkembang, sehingga pemaknaan-pemaknaan identitas terus mengalami
perubahan. Makna identitas Kulit Hitam atau Afrika misalnya, terus menerus berubah
berkaitan dengan politik yang selalu diartikulasi ulang dan direkaulang (Kanneh, 1998).
Makna identitas Tionghoa Indonesia juga terus berubah (Afif, 2012), dan demikian juga
halnya dengan identitas Dayak (Maunati, 2004) dan identitas Bali (Dwipayana, 2005).
Meskipun pemaknaan identitas dapat berubah, namun kebudayaan menjadi media dalam
penandaan dan pelestarian identitas di dalam kelompok dan untuk membedakannya dengan
kelompok lain.
Identitas sebagai konstruksi sosial hadir dalam representasi kultural dan akulturasi,
sehingga tidak mungkin eksis di luar itu (Barker, 2005). Dengan hadirnya identitas dalam
representasi budaya dan akulturasi, tafsiran-tafsiran mengenai identitas pun tidak pernah
berhenti dan tidak mungkin final. Itu membuktikan bahwa tafsiran tentang identitas akan
terus diperbaharui di dalam wacana sejarah dan kebudayaan (Piliang, 2002). Wacana
kebudayaan bisa beraneka ragam dan sangat mungkin saling bertentangan. Wacana tertentu
bahkan dapat menjadi dominan atau sebaliknya bergantung pada ada atau tidaknya
kekuasaan pendukungnya.
E. 1. 2. Wacana, Kekuasaan dan Perlawanan
Untuk memahami wacana21 identitas dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan di sini
digunakan sudut pandang Foucault (1980) tentang wacana sebagai sistem representasi yang
mereproduksi objek-objek pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada objek yang memiliki
makna di luar wacana (Foucault, 1980). Maksudnya, segala sesuatu itu bermakna karena
diwacanakan. Menurut Foucault wacana selain berfungsi mendefinisikan (termasuk
20
21
Misalnya kita mengenal adanya kelompok Muslim Bali, Hindu Bali, Hindu Jawa, dan Muslim Sasak.
Wacana adalah terjemahan dari kata discourse dalam bahasa Inggris. Secara etimologi istilah ini berasal dari
dua kata dalam bahasa Latin: dis dan curere. ‘dis’ berarti ‘dalam arah yang berbeda’ dan ‘curere’ berarti
berlari (Cavallaro, 2001: 163).
22
identitas), juga memiliki kemampuan untuk membatasi dan mengeksklusi cara-cara lain di
luar wacana yang berlaku. Melalui eksklusi, hal-hal tertentu dikeluarkan dari anggapan
sebagai suatu yang nyata dan layak diperhatikan. Apa yang nyata dan yang layak merupakan
hasil konstruksi, sehingga wacana akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Sebagai
contoh, bagi orang Mentawai di bagian selatan, laggai dimaknai ‘kampung’, sedangkan bagi
orang Siberut22, laggai dimaknai sebagai kemaluan laki-laki. Oleh karena itu dianggap 'kotor'
jika kata itu disebut-sebut sehingga tidak layak untuk dijadikan nama pengganti desa.
Makna-makna yang berbeda tersebut dapat berubah jika relasi kekuasaan berubah,
karena setiap wacana tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan kekuasaan (Foucault,
1980; Alam, 1999). Kekuasaan (power) adalah kemampuan untuk menstruktur tindakan
orang lain ke dalam bidang tertentu dan selalu diproduksi dalam relasi (Foucault, 1972: 427).
Sebagai strategi, kekuasaan itu dipraktikkan dalam hubungan antarindividu di dalam
masyarakat dan dinegosiasikan melalui interaksi. Dalam suatu konteks sosial, wacana
memiliki kekuatan untuk menyusun dan mempengaruhi pemahaman pelaku (kita) tentang
realitas, termasuk gagasan tentang identitas kita. Oleh karena itu, realitas merupakan suatu
yang dikonstruksi.
Persoalan identitas sebagaimana juga wacana tentang kebudayaan, berkaitan dengan
kepentingan dan kekuasaan.
Kekuasaan mendukung wacana-wacana tertentu menjadi
wacana dominan, sementara itu, wacana lainnya akan ‘terpinggirkan’ (marginalized) atau
‘terpendam’ (submerged) (Alam, 1999: 8; Eriyanto, 2001: 77). Wacana tentang kebudayaan
di dalam masyarakat yang beragam sangat memungkinkan untuk saling bertentangan.
Sebuah wacana yang besar bisa terdiri dari bermacam sub wacana yang tidak saja saling
berhubungan tetapi juga saling berkontestasi untuk mencapai pengakuan akan 'kebenaran'.
Di sini lah pentingnya untuk memahami keterlibatan 'subjektivitas' dalam wacana
sebagaimana ditenggarai oleh Alam (1999) karena menjadikan kita dapat melihat setiap
wacana tentang kebudayaan tidak terlepas dari kekuasaan dan beragam kepentingan.
Kepentingan individual atau pun kelompok akan tampak dari adanya usaha untuk menelusuri
22
Kata Siberut dan Sabirut di dalam tulisan ini digunakan secara bergantian. Istilah ini untuk merujuk pada
nama pulau, orang-orang yang mendiami Pulau Siberut dan kumpulan orang-orang yang dianggap berasal
dari Lembah Siberut. Lembah Siberut adalah salah satu lembah di pesisir timur Pulau Siberut yang di Pulau
Siberut sendiri dikenal sebagai Sabirut atau orang Sabirut. Sedangkan dalam relasinya dengan orang-orang
di luar Pulau Siberut, seperti orang di Pulau Sipora dan Pulau Pagai mereka menyebut orang Siberut atau
Sabirut untuk merujuk semua penghuni Pulau Siberut. Dalam konteks pemakaian oleh orang-orang Pulau
Pagai dan Sipora istilah Siberut dan Sabirut merujuk pada nama pulau Siberut dan semua penghuni Pulau
Siberut.
23
sejarah yang sama atau disama-samakan, termasuk sejarah asal-usul. Kepentingan lain
adalah tindak penyamaan dan upaya untuk mengklaim ‘sesuatu’ sebagai identitas mereka
merupakan usaha yang bersifat selektif dan politis, dimana aktor melakukan pilihanpilihannya. Adapun pilihan-pilihan merujuk pada eksternalitas yang telah diinternalisasi oleh
agen (Bourdieu, 1994). Oleh karena itu penting untuk memahami mengapa pembedaanpembedaan yang terkait dengan pengalaman itu dimunculkan dalam wacana dan apa tujuan
(kepentingan) tertentu di balik tindakan pewacana.
Berkaitan dengan usaha yang selektif dan politis dalam wacana identitas dapat kita
lihat misalnya mengenai isu pengukuhan lokalitas melalui pilihan untuk mengusung nama
laggai sebagai pengganti desa. Mengapa laggai yang dipilih oleh para pengusungnya, bukan
pulaggajat seperti yang lazim digunakan orang Mentawai di Siberut? Usaha mengusung
nama yang dianggap paling tepat dan layak untuk sistem pemerintahan yang akan digunakan
di Mentawai mengandung perdebatan. Dalam perdebatan itu orang-orang berusaha
membangun klaimnya masing-masing dengan cara mencari atau menelusuri asal-usul yang
sama, nenek moyang, nilai-nilai luhur, maupun tradisi yang sama (disamakan atau yang
dibayangkan sama). Pada akhirnya, tindak penyamaan itu akan memunculkan ide tentang
pembedaan antara siapa yang 'orang asli' dan siapa yang 'pendatang'. Usaha tersebut dapat
dikatakan merepresentasikan padangan subjek.
Melalui usaha tindak penyamaan dan pembedaan itu dapat dipahami bahwa di antara
dua atau lebih entitas sosial menunjukkan suatu hakikat identitas yang dibangun bersifat
relasional (Simatupang, 2006), kendati tindak penyamaan dan pembedaan itu dapat muncul
hanya karena dibayangkan. Dengan dibayangkan, identitas komunitas tersebut sesungguhnya
bukan merupakan penemuan, melainkan hasil suatu proses yang berisi usaha anggota
komunitas yang bagi sebagian besar orang mungkin tidak saling mengenal (Anderson, 2002).
Mereka juga tidak saling bertatap muka, bahkan tidak pernah saling mendengar satu sama
lain untuk mendefinisikan diri mereka sebagai anggota suatu komunitas yang lebih besar
(Anderson, 2002). Perlu dicermati bahwa tidak semua tindak penyamaan dan pembedaan
tersebut dapat dilakukan hanya dengan dibayangkan saja. Hal ini dikarenakan globalisasi
juga mempermudah tersedianya ruang untuk konstruksi identitas, dimana pertukaran barang
ataupun simbol menjadi lebih leluasa. Ditambah lagi, perkembangan teknologi transportasi
dan komunikasi membuat pertemuan berbagai kebudayaan semakin mudah terjadi, termasuk
untuk penyebaran wacana tertentu seperti wacana indigenous rights.
24
Melalui pertemuan beragam budaya, pengalaman dan proses belajar tentang relasi
dapat berlangsung. Menurut Horowitz (1981) proses belajar juga turut berperan membentuk
identitas etnik. Proses itu menguatkan pandangan Hall (Piliang, 2001) bahwa identitas
didefinisikan sebagai cara sebuah kebudayaan menafsirkan posisi dirinya di dalam rentang
sejarah dan dalam relasinya dengan kebudayaan lain. Penafsiran tersebut merupakan upaya
bagaimana kita memandang diri kita tidak sama atau boleh jadi dipertentangkan dengan yang
lain. Artinya, identitas dapat dilihat dalam kaitannya dengan praktik resistensi karena
identitas dapat dimunculkan untuk melawan kelompok tertentu (Castells, 2000; Eriksen,
1993; Wolfers, 2010), walaupun cara perlawanan bisa berbeda-beda (khusus). Hal ini dapat
terjadi, karena sifat dinamis dari konstruksi identitas. Melawan kelompok luar dengan
menekankan pada perbedaan yang dimiliki oleh satu etnik merupakan fokus perhatian dari
politik identitas yang dimaksud. Sebagaimana dikemukakan Heller (dalam Abdilah,
2002:16) politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya terletak pada
penekanan perbedaan sebagai kategori politik yang utama.
Penekanan pada perbedaan antara kelompok 'kita' dengan others juga dapat muncul
atau bermakna sebagai sebuah kekhawatiran atau ketakutan. Itu menunjukkan terminologi
identitas ditempatkan pada posisi defensif karena ada perasaan terancam. Seperti halnya
kekuasaan (power), identitas juga dapat digunakan untuk melawan kelompok lain
(dipandang lain), sekalipun kelompok-kelompok itu sebenarnya memiliki latar belakang
etnik yang sama. Dengan demikian perlawanan pada dasarnya adalah hubungan defensif.
Ini dapat terjadi dalam situasi dimana bentuk-bentuk kekuasaan budaya tersebut muncul dari
suatu sumber yang jelas-jelas dialami sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan sebagai
liyan (Bannet dalam Barker, 2005: 359). Dalam studi ini misalnya, wacana Nagari di
Sumatera Barat sebagai salah satu wacana penting di era Otonomi Daerah, menjadi suatu
yang bersifat eksternal dan sekaligus liyan bagi Mentawai. Oleh karena itu, perlawanan akan
muncul ketika sesuatu yang dianggap liyan atau kolektivitas liyan (Minangkabau) akan
mengalahkan kolektivitas kelompok sendiri (Mentawai).
Perlawanan atau resistensi dalam pandangan Foucault (1982: 30) bisa muncul dalam
tiga bentuk, yaitu perlawanan atas dominasi (etnik, agama, dan kelas), perlawanan atas
eksploitasi yang memisahkan individu dari apa yang diproduksinya, dan perlawanan atas
subjektivitas. Subjek adalah hasil bentukan struktur yang berdampak pada pola pemikiran
yang dualistis, cenderung mengeksklusi yang lain (Kristiatmo, 2011). Tindak eksklusi dalam
wacana dilakukan melalui kata-kata yang penggunaannya dianggap tabu (misalnya
25
pembagian antara apa yang dianggap wajar dan tidak) (Foucault, 1981: 52). Wajar dan tidak
wajar, benar dan tidak benar, boleh dan tidak boleh, layak dan tidak layak merupakan
kategori buatan manusia yang menjadi subjek, karena adanya praktik pembagian yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek menciptakan klaim kebenaran melalui
ucapan dan teks dalam memaknai realitas sosial. Klaim kebenaran diciptakan sebagai bentuk
bekerjanya kekuasaan sebagai wacana yang dapat mempengaruhi praktik-praktik sosial.
Perlawanan itu dapat juga dilakukan dengan memunculkan wacana lain, yakni wacana
yang bertentangan dengan wacana dominan (doxa) dari kelompok tertentu. Baik wacana itu
dilakukan melalui wacana tulis maupun wacana lisan. Menurut Bourdieu (dalam Fashri,
2007: 124), kelompok yang memiliki wacana dominan (doxa) akan lebih leluasa dalam
memaksakan visi dan normanya kepada kelompok yang tidak dominan (subordinat).
Dominasi dengan cara-cara pemaksaan visi maupun norma mengakibatkan kelompok yang
tidak dominan juga berwacana untuk melakukan perlawanan terhadap wacana dominan.
Berarti wacana yang mereka bangun menjadi wacana perlawanan.
Menurut Foucault (1982), walaupun kekuasaan tersebut tidak tampak, ia selalu akan
memunculkan peluang untuk resistensi sebagai bagian dari relasi kekuasaan. Oleh Bourdieu
(1992: 170), kekuasaan yang tidak tampak ini disebut sebagai simbolic power yang bekerja
dengan penggunaan simbol-simbol secara halus. Kekuasaan yang mengambil bentuk yang
halus ini hampir tidak dikenali (misrecognition) oleh kelompok yang didominasi, namun
sesungguhnya bentuk ini menyembunyikan praktik dominasi (Bourdieu, 2001:1). Ini bisa
dalam bentuk bahasa, karena bahasa adalah salah satu instrumen penting dalam praktik
pewacanaan yang bisa hadir dalam semua arena sosial. Dalam melihat hubungan kuasa dan
bahasa, salah satunya melalui cara penciptaan realitas melalui bahasa yang merupakan
bentuk kuasa yang paling halus, dan inilah yang dimaksud Bourdieu sebagai simbolic power
(Aunullah, 2006: 5). Pewacanaan yang dilakukan dalam melawan wacana lain berhubungan
dengan penafsiran masing-masing pewacana dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu.
Makna ada dalam suatu produksi sosial dan suatu praktik yang mengandung pertentangan
sosial (Hall dalam Eriyanto, 2001: 37). Pemaknaan tentang identitas seringkali juga
berkaitan dengan hal yang bersifat politis. Oleh karena itu, perubahan-perubahan politis yang
terjadi ikut mempengaruhi pewacanaan identitas itu sendiri. Wacana menjadi sebuah praktik,
ketika sesuatu itu memproduksi yang lain, baik dalam bentuk gagasan, konsep maupun
tindakan.
26
Sejumlah wacana juga dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologis
yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga dan berbagai macam modus penyebaran
pengetahuan (Foucault, 1980). Kekuasaan itu tidak dirumuskan sebagai kekuatan pengendali
yang terpusat karena kekuasaan tersebut tersebar pada semua level bangunan sosial,
kekuasaan bersifat generatif, yakni merupakan produksi dari relasi sosial dan identitas
(Foucault dalam Barker, 2005: 21). Dengan demikian dapat dipahami, kekuasaan juga
merupakan proses yang melibatkan agensi, wacana dan praktik yang mengalir dari bawah ke
atas (Foucault dalam Agger, 2003: 283). Selain itu, kekuasaan juga menunjukkan relasi
antaraktor (subjek) yang juga bisa berubah. Oleh karena itu dapat dipastikan, wacana
identitas dapat berubah dan dapat diubah bergantung pada konteksnya: kekuasaan dan
kepentingan yang bermain di belakangnya. Dalam kajian ini, keseluruhan rangkaian dari
proses negosiasi, perebutan klaim kebenaran dalam praktik pemaknaan dan bagaimana
subjek direpresentasikan, dilihat sebagai bangunan diskursif.
Wacana identitas (ke-Mentawai-an) di sini dikaji melalui konsep kekuasaan dan juga
praktik sosial. Ke-Mentawai-an berhubungan dengan kekuasaan, dan orang yang memiliki
kuasa membangun wacana yang dapat mensubordinasikan kepentingan yang lain, contohnya
pembangunan nasional. Dengan alasan kepentingan nasional yang merupakan kepentingan
kelompok dominan, wacana pembangunan yang dibangun oleh pemerintah dan lembagalembaga lain telah mensubordinasikan kepentingan rakyat (Abdullah, 1999: 23). Pada saat
wacana dominan menguasai pasar, ia pun memiliki otoritas untuk mendefinisikan the Other
(Bourdieu, 1992). Sejauh mana wacana dominan ingin dipertahankan oleh kelompok
tertentu, kelompok lain berupaya menggugatnya (melawan). Seperti halnya kekuasaan,
perlawanan terhadap kekuasaan juga ada di mana-mana (Foucault, 1982; Ritzer dan
Goodman, 2008). Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya ada di antara para elit,
kekuasaan juga ada di antara orang kebanyakan yang aktif membangun wacana-wacana
perlawanan. Selama masih ada kekuasaan, perlawanan pun akan selalu ada seperti apa pun
bentuknya, terutama di saat negosiasi tidak berjalan.
Berkenaan dengan persoalan identitas, perlawanan dan kekuasaan ini Castells (2000)
menjelaskan bahwa konstruksi sosial dari identitas selalu muncul dalam sebuah konteks yang
ditandai oleh hubungan-hubungan kekuasaan. Terkait persoalan itu, lebih jauh lagi Castells
mengajukan tiga bentuk dan asal-usul dari bangunan identitas, yaitu: 1) Identitas yang sah
(legitimizing identity) yang diintrodusir oleh institusi dominan masyarakat untuk meluaskan
dan merasionalkan dominasi mereka, contohnya otoritas dan dominasi; 2) Identitas
27
perlawanan (resistance identity) ditimbulkan oleh aktor-aktor yang dalam situasi atau kondisi
yang direndahkan martabatnya atau distigmatisasi oleh logika dominasi, contohnya politik
identitas; dan 3) Identitas proyek (project identity), yakni ketika aktor sosial atas dasar
budaya material mana pun tersedia bagi mereka untuk membangun identitas baru yang
meredifinisi posisi mereka di dalam masyarakat, contohnya feminism (2000: 7-8). Asal-usul
dan bentuk bangunan identitas yang ditandai oleh relasi kekuasaan tersebut tidaklah bersifat
kaku, melainkan sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat memungkinkan jika resistance
identity tersebut juga dapat digunakan atau diubah menjadi project identity atau legitimizing
identity diubah menjadi resistance identity.
E. 2. Landasan Teori
Signifikansi teoritis penelitian ini berusaha melihat hubungan kekuasaan dan
bagaimana kekuasaan dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi ke-Mentawai-an.
Orang-orang menggunakan wacana dan klaim kebenaran sebagai rujukan pandangan yang
dianggap paling valid dalam mempersoalkan fenomena sosial. Sebagai contoh, terkait
penciptaan sistem pemerintahan terendah setempat dan isu-isu yang melatarbelakanginya.
Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana model relasi kekuasaan dalam
konteks rancangan Perda Laggai diterjemahkan orang-orang Mentawai untuk memaknai
identitas mereka.
Konsep identitas selalu hadir dalam wacana kebudayaan, maka kebudayaan itu tidak
dapat dilepaskan dari proses pembentukan kekuasaan. Artinya pembentukan identitas dapat
berubah, salah satunya apabila relasi kekuasaan juga berubah. Sejalan dengan itu Ortner
menyebutkan, perlu menempatkan kekuasaan sebagai kerangka kerja teoritis yang diperlukan
dalam studi kritis, terutama mengenai ketidaksetaraan dan dominasi (Ortner, 2006: 4).
Pendukung kebudayaan merupakan pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan dan
kekuasaan. Sebagai subjek yang aktif, setiap aktor membangun makna dan sekaligus
bertindak secara strategis di dalam praktik karena masing-masing memiliki kesadaran
subjektif. Strategi sebagai produk dari habitus dilakukan untuk penyesuaian atau perlawanan
terhadap kekuasaan yang ada di dalam arena. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan
teori praktik (theory of practice) yang dikembangkan oleh Bourdieu (1977; Jenkins, 2004).
Dalam mengembangkan teori praktik, Bourdieu membedakan antara konsep praktiknya
dengan konsep tindakan dari Weber yang cenderung melihatnya sebagai cerminan ide yang
terkandung dalam kebudayaan pelaku. Suatu pandangan yang juga diwarisi oleh Geertz
dalam pendekatan interpretifnya (Alam, 1998: 5; 1999: 7). Konsep praktik menurut
28
Bourdieu, menekankan hubungan timbal balik antara pelaku yang memiliki kesadaran
subjektif dan struktur objektif yang mencakup kebudayaan si pelaku sebagai sistem
pengetahuan yang diwarisi dari generasi ke generasi (Bourdieu, 1977: 83). Hubungan timbal
balik antara pelaku yang berkesadaran subjektif dan struktur objektif digambarkan Bourdieu
sebagai: 1) struktur objektif direproduksi para pelaku secara terus menerus di dalam praktik
pada kondisi historis tertentu, 2) dalam proses tersebut, para pelaku mengartikulasikan dan
mengapropriasi simbol-simbol budaya yang terdapat dalam struktur objektif sebagai
tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu, 3) sehingga proses timbal balik antara
praktik dan struktur objektif secara terus menerus dapat menghasilkan perubahan maupun
kontinuitas (Bourdieu, 1977: 83; Alam 1998: 5; 1999: 7).
Berangkat dari hal di atas, maka muncul pertanyaan, apakah Foucault dan Bourdieu
memiliki kesamaan dalam memandang kebudayaan? Keduanya sama-sama melihat makna
sebagai suatu yang dikonstruksi. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Lewellen (2002:
49), keduanya, baik Foucault maupun Bourdieu, cenderung melihat kebudayaan sebagai
sistem kognitif, simbolik, dan sistem makna yang diciptakan. Jika konsep wacana Foucault
memiliki banyak karakteristik kebudayaan, demikian juga halnya Bourdieu dengan konsep
habitusnya sebagai internalisasi tak sadar dari struktur objektif (kebudayaan) dari masyarakat
(Lewellen, 2002: 49). Bagi Bourdieu, kebudayaan kurang lebih adalah habitus, dan
kebudayaan menjadi seperangkat nilai yang diinternalisasikan dalam diri sedemikian rupa
sehingga menjadi tidak sadar (Zizek dalam Kristiatmo, 2011: 80). Ortner (2006) juga
berpendapat bahwa habitus memiliki kesamaan dengan gagasan kebudayaan yang dapat
dipahami melalui konsep internalisasi. Jika demikian apakah pandangan Foucault dan
Bourdieu ada kesamaan dengan Geertz (1973) yang juga memandang kebudayaan sebagai
sistem simbol yang mempengaruhi dan membentuk dunia sosial? Kesamaan pandangannya
karena kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan karena menyediakan model dari apa
yang dianggap sebagai realitas dan pola-pola bagi prilaku. Hanya saja pandangan Geertz
melihat proses kebudayaan terlepas dari relasi kekuasaan.
Antara Foucault (1977) dan Bourdieu (1977), memiliki kesamaan cara pandang dalam
melihat hubungan kekuasaan dan praktik. Artinya keduanya berpandangan bahwa kekuasaan
muncul di dalam relasi sosial. Teori praktis menjadi penting di sini, karena wacana sendiri
menyatukan bahasa dan praktik. Teori praktis menempatkan kembali aktor dalam proses
sosial tanpa menghilangkan bidikan terhadap struktur yang lebih luas, tidak hanya
mendukung, tetapi juga mengubah tindakan sosial (Ortner, 2006: 3). Kebudayaan selalu
29
terwujud dalam praktik. Salah satu praktik yang berfungsi mengonstruksi kebudayaan ialah
praktik kewacanaan. Oleh karena itu, kebudayaan sebagai sesuatu yang dikonstruksi, erat
kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan para pewacana (Alam, 1999).
Lebih jauh Bourdieu (1992) menjelaskan bahwa praktik merupakan produk dari relasi
antara habitus sebagai produk sejarah dan ranah. Bourdieu menggunakan konsep habitus ini
untuk memahami proses pembelajaran dan pengalaman yang ditemui individu dalam
kehidupannya sebagai bekal pengetahuan baginya untuk bertindak (Jenkins, 2004). Oleh
karena itu, keterlibatan orang-orang (aktor) sebagai subjek dalam proses konstruksi budaya
merupakan hal yang penting (Bourdieu, 1978). Adakalanya, ruang sosial tertentu itu sendiri
tidak memberikan tempat bagi semua individu yang sama sekali tidak memiliki modal
ekonomi maupun kultural untuk bertarung di ranah ini. Perbedaan modal yang dimiliki
menjadikan pertarungan di dalam ranah tidak seimbang, karena alat dominasi bergantung
pada jumlah dan bentuk modal yang dimiliki seseorang. Agak berbeda dari Foucault, bagi
Bourdieu kuasa tidaklah tersebar di mana-mana, namun tetap terkonsentrasi di wilayahwilayah tertentu dalam dunia sosial, terutama dalam institusi yang menjamin berlangsungnya
reproduksi berbagai jenis modal. Institusi ini antara lain bisa dalam rumah tangga (lalep),
klen (uma), dan pemukiman (barasi). Oleh karena masing-masing memiliki modal yang
berbeda, maka wacana yang dibangun berkaitan dengan kekuatan modal yang dimiliki. Hal
yang sama juga ada dalam negosiasi dan perlawanan dimana akan disesuaikan dengan jenis
modal yang dimiliki dan kekuatan modal ini pun dapat berubah-ubah.
Pewacanaan ke-Mentawai-an itu masih akan terus dibangun dan diperdebatkan, dan
dalam proses pengonstruksian identitas terkait dengan perubahan yang terus berlanjut.
Makna identitas tidak hanya ada dalam struktur bahasa, namun juga ada dalam wacana
sebagaimana yang dilakukan para aktor/pelaku wacana. Oleh karena itu wacana identitas
dapat dilihat sebagai ranah yang penuh konflik atau pertarungan, pemaknaan, klaim dan juga
negosiasi. Dengan demikian, makna menjadi sebuah produksi yang dikontrol (dibatasi),
dikembangkan, dikontestasikan dan diperebutkan. Subjektivitas atau kepentingan bermain
dalam proses konstruksinya, sehingga pemaknaan yang dibangun akan bersifat plural.
Pemikiran-pemikiran yang dijabarkan di atas akan dijadikan pijakan untuk melihat
persoalan wacana identitas di Mentawai. Langkah awal yang akan dilakukan adalah
menelusuri persoalan terkait usaha mengganti bentuk pemerintahan desa di Mentawai
30
menjadi laggai23, walaupun pemerintahan laggai ini belum pernah ada sebelumnya.
Kelompok-kelompok elit terpelajar dari Sipora dan Pagai memunculkan istilah laggai
tersebut, sementara di level orang kebanyakan (paling tidak di Siberut) istilah itu ditolak.
Wacana tersebut kemudian diusung kembali oleh kelompok elit. Untuk itu, perlu mengkaji
lebih dalam bagaimana masyarakat Mentawai memainkan peranannya dalam pembentukan
wacana identitas (ke-Mentawai-an) yang tidak hanya terkait dengan perbincangan laggai,
tetapi juga mengenai gagasan orisinalitas, perbicangan asal-usul dan praktik-praktik budaya
di antara mereka. Bagaimana pula kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, bertentangan
dalam membangun klaim-klaim kebenaran (pemaknaan) itu dinegosiasikan oleh para pelaku.
Keseluruhan rangkaian dari proses negosiasi, perebutan klaim kebenaran dan bagaimana
orang Mentawai sebagai agen dan subjek membuat praktik-praktik pembagian (pembedaan)
yang mengeksklusi yang lain, serta bagaimana subjek direpresentasikan menjadi bagian dari
pengonstruksian wacana ke-Mentawai-an itu. Melalui perdebatan-perdebatan di antara orang
Mentawai di Barasi Muntei akan menunjukkan bahwa mereka terlibat aktif dalam
pemaknaan-pemaknaan identitas yang dibangun.
Jadi identitas Mentawai tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis, melainkan entitas
yang dinamis, cair dan sekaligus berubah-ubah (situasional), serta selalu mengalami
perjumpaan dengan 'yang Lain'. Dalam perjumpaan dengan yang lain itu berlangsung proses
negosiasi dan resistensi, namun karena identitas sekaligus merupakan arena pertarungan
maka dalam pemaknaan-pemaknaan akan identitas itu klaim-klaim kebenaran saling
diperebutkan. Konstruksi identitas di sini adalah konstruksi di dalam dan melalui wacana.
Wacana dan identitas bersifat dialektis, dimana identitas itu dikonstruksi di dalam wacana
dan sebaliknya pewacanaan dilakukan untuk mengonstruksi identitas. Wacana perempuan di
sini, meski bukan dalam perdebatan yang sama dengan kaum laki-laki (laggai dan
pulaggajat), tetapi dari studi ini penting untuk memberi perhatian terhadap suara-suara
perempuan di barasi dalam perdebatan identitas dan pandangan mereka tentang relasinya
dengan Sasareu
23
Pemerintahan Laggai ini belum pernah dijalankan sebelumnya di Mentawai, baik sebelum penerapan model
pemerintahan desa maupun sebelum pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari pernah diberlakukan di
Mentawai, karena Mentawai sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, dan itu
membuktikan betapa kuatnya dominasi Minangkabau terhadap Mentawai. Berbeda dengan
pemerintahanNagari dalam masyarakat Minangkabau yang secara historis memang telah ada dan dijalankan
sebelum diberlakukannya penyeragaman pemerintahan desa. Format pemerintahan laggai ini dirancang oleh
kelompok elit Mentawai yang didominasi oleh orang-orang Mentawai Sipora dan Pagai yang oleh orang
Mentawai Siberut disebut sebagai Sakalagan (lihat Delfi, 2005).
31
F. Metode Penelitian
F. 1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan dengan fokus di barasi
24
, yaitu Barasi Muntei untuk memotret
persoalan perdebatan identitas. Barasi ini dipilih tidak saja karena penolakan warganya pada
Ranperda Laggai, tetapi juga karena Barasi Muntei berada tidak jauh dari pusat Kecamatan
Siberut Selatan dan dermaga kapal, sebagai gerbang masuknya Sasareu ke Siberut. Posisinya
yang demikian strategis, memungkinkan untuk melihat interaksi dengan Sasareu. Di
samping itu, barasi ini merupakan salah satu kampung relokasi yang sekaligus daerah transit
untuk masuk ke wilayah pedalaman Siberut Selatan. Penghuni barasi ini masih memiliki
hubungan yang relatif kuat dengan kelompok uma yang ada di hulu sungai dan masih
dijumpai praktik ritual Sabulungan sebagai penanda identitas orang Mentawai. Selain itu,
barasi ini tidak hanya didiami oleh kelompok orang yang lembah asalnya berbeda tetapi juga
oleh Sasareu. Barasi menjadi penting untuk melihat pembentukan identitas dalam konteks
kekinian.
Penelitian juga dilakukan dengan mengunjungi dan tinggal di beberapa pemukiman
'tradisional' uma, di Badmara di bagian hulu Lembah Siberut dan Attabai di Lembah
Rereiket. Penulis juga mengunjungi dan tinggal di barasi atau dusun yang ada di daerah
aliran Sungai Rereiket, antara lain; Rokdog, Madobag dan Ugai yang menjadi daerah pilihan
kunjungan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan demikian, barasi dan
kampung-kampung yang dipilih dapat dikatakan sebagai representasi dari kebudayaan
Mentawai di Pulau Siberut yang dinamis. Selain berkunjung dan melakukan observasi,
wawancara dengan orang tertentu di kampung tersebut juga dilakukan.
F. 2. Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa metode yang dipakai dalam proses pengumpulan data, di antaranya:
studi literatur, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam. Selain itu juga
mengumpulkan teks-teks media yang terkait dengan wacana penolakan Perda Nagari dari
koran lokal Puailiggoubat.
Studi literatur merupakan metode yang sangat penting digunakan untuk memahami
secara lebih jauh dimensi-dimensi kebudayaan Mentawai yang telah ditulis dan dipaparkan
oleh peneliti sebelumnya baik itu oleh peneliti asing (Barat) maupun penulis Indonesia.
24
Barasi adalah kampung yang terbentuk karena adanya program relokasi. Barasi Muntei merupakan salah
satu kampung relokasi di Kecamatan Siberut Selatan dan merupakan pusat Desa Muntei yang memiliki 3
dusun yang letaknya berjauhan. Penjelasan selanjutnya tentang penamaan barasi dan dusun-dusun lainnya
dapat dilihat di Bab II.
32
Literatur-literatur tentang Mentawai dalam berbagai fokus kajian dan cara pandang dipelajari
secara lebih seksama. Berangkat dari studi pustaka tersebut dan data-data yang terkumpul di
lapangan yang dilakukan sejak Maret tahun 2007 sampai April tahun 2008 dalam beberapa
kali kunjungan, membantu penulis menemukan bagaimana relasi-relasi antara berbagai
kekuatan yang mempengaruhi atau mendorong munculnya wacana ke-Mentawai-an saat ini.
Observasi partisipasi dilakukan untuk mengamati berbagai fenomena
yang
berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu maka bagaimana seseorang merespons
perilaku orang lain di luar kelompok maupun dalam kelompoknya dalam ruang dan waktu
tertentu menjadi salah satu sasaran observasi partisipasi ini. Begitu juga halnya dengan siapa
aktor-aktor yang berperan (pelaku wacana), status sosial apa yang dimilikinya, bagaimana
cara-cara yang dilakukan oleh aktor atau kelompok tertentu dalam mempengaruhi individu
atau kelompok lain dalam kehidupan sehari-hari dalam pembentukan wacana identitas juga
dilakukan. Sebagaimana dianjurkan Foucault (dalam Ritzer, 2005: 67-78), penting
menyelidiki peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang
diperbincangkan atau pun yang ditulis.
Pemahaman bagaimana sudut pandang orang Mentawai dan kaitannya dengan identitas
budaya, pandangan dan penolakan mereka terhadap konstruksi identitas yang diberikan oleh
orang-orang luar (Sasareu). Hal ini dilakukan dengan dua cara: pertama dengan membaca
secara seksama teks-teks media untuk menemukan tema-tema yang menonjol, kemudian
dicatat. Selanjutnya, menemukan hubungan antara isu-isu yang berkembang dan kaitannya
dengan bagaimana formasi diskursif terbentuk yang kemudian membangun wacana tentang
ke-Mentawai-an. Kedua, mewawancarai mereka sambil mengikuti kegiatan-kegiatan orang
Mentawai. Hal ini tidak hanya di barasi, tetapi juga ikut serta pergi ke ladang, ke pulaupulau kecil (di bagian tenggara) dimana mereka sering mengolah kopra, ke penyulingan
nilam, dan ke pengolahan sagu. Melalui cara-cara seperti itu, akan lebih leluasa memahami
pandangan mereka tentang pekerjaan dan lingkungan mereka. Kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan ritual kelompok juga saya ikuti, antara lain: ritual peresmian bangunan uma
Aman25 Tompu, ritual pengobatan kerei Aman Pius, ritual pemberian nama (abinen) anaknya
Inan Hopu dan anaknya Inan Bose, ritual kematian Inan Ledo. Keikutsertaan dalam kegiatan
25
Kata aman yang digunakan di dalam tulisan ini adalah untuk seorang laki-laki yang sudah memiliki anak,
biasanya akan dipanggil dengan sebutan anak pertama. Demikian juga halnya dengan kata inan dalam
tulisan ini digunakan untuk seorang perempuan yang sudah memiliki anak. Baik kata aman maupun inan
yang diikuti dengan nama anak masing masing dicetak miring. Sebagai informan sebutan itu tetap digunakan
dan ditulis dengan huruf miring karena di dalam pembicaraan sehari-hari panggilan itu tetap digunakan.
33
tersebut membawa saya pada pemahaman mengenai bagaimana orang-orang barasi
memaknai ritual tersebut dalam hubungannya dengan ke-Mentawai-an.
Guna mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pandangan-pandangan aktor
tentang kelompok mereka, baik sebagai anggota uma maupun warga barasi dilakukan
dengan cara ikut berkumpul dengan mereka di uma-uma, warung-warung, posyandu26,
gereja, di rumah-rumah penduduk/lalep (terutama yang ada televisi). Keikutsertaan lain ialah
dengan ikut ambil bagian mengangkut pasir bersama ibu-ibu dan remaja putri untuk
pembangunan Gereja Katolik. Beberapa kali turut mempersiapkan minuman dan makanan
ringan untuk warga yang ikut kegiatan tersebut.
Keterlibatan itu menantang pemahaman akan Bahasa Mentawai agar peneliti dapat
menangkap obrolan-obrolan mereka. Beruntung penulis telah mempelajari Bahasa Mentawai
sejak sebelum melakukan penelitian untuk tesis master di Universitas Gadjah Mada. Selain
itu, penulis sering ikut kegiatan ibu dan remaja putri seperti: menangkap ikan di sungai, laut
dan rawa-rawa hutan sagu, mengambil bambu atau daun sagu untuk memasak sagu, mencari
kayu bakar, mencari ulat sagu, kerang sungai, bersama-sama mencuci dan mandi di sungai.
Wawancara sering dilakukan dengan kaum perempuan pada saat ikut dalam kegiatan
bersama mereka. Dalam penelitian ini, kadangkala wanita sering kali diabaikan, walaupun
dalam kehidupan sehari-hari para wanita seringkali jauh lebih paham tentang dinamika yang
terjadi dalam masyarakat (Sairin, 2006: 96). Keikutsertaan tersebut memberi peluang untuk
mengetahui perbincangan mereka, khususnya ‘gosip-gosip’ yang berkembang di antara kaum
perempuan dan juga pandangan perempuan mengenai ‘ke-Mentawai-an’ itu sendiri dalam
hubungannya dengan Sasareu. Semua hal tersebut menjadi sasaran dalam metode wawancara
dan partisipasi observasi yang dilakukan sehingga pemahaman tentang wacana identitas
menjadi semakin beragam.
Sebagai perempuan tidak mungkin penulis terlibat di semua kegiatan yang ada,
terutama kegiatan yang menjadi beban atau tugasnya laki-laki. Kaum laki-laki yang tidak
mau penulis terlibat dengan kegiatan tertentu biasanya mereka mengatakan kalau hal itu
berat buat seorang perempuan, misalnya: mencari rotan ke hutan-hutan yang cukup jauh dari
pemukiman, menebang kayu besar untuk membuat sampan atau tiang-tiang rumah. Selama
berada di lokasi penelitian, kegiatan laki-laki yang diikuti adalah memberi makan babi dan
ayam, menebang kayu untuk membangun rumah dan jembatan, membersihkan ladang kakao,
26
Untuk Posyandu ini ada rumah warga barasi yang dijadikan tempat untuk menimbang bayi dan juga untuk
membagikan makanan tambahan untuk anak-anak.
34
ladang pisang dan mengambil daun sagu untuk atap (tobat). Untuk kegiatan yang memang
tidak memungkinkan untuk terlibat di dalamnya maka penulis hanya mewawancarai orangorangnya saja.
Untuk mendalami informasi berkenaan dengan konstruksi dan rekonstruksi sedemikian
rupa, wawancara mendalam (in-depth interview) digunakan dengan memusatkan perhatian
pada pertanyaan mengapa aktor-aktor merespon pernyataan-pernyataan dan perilaku orang
lain, dan bagaimana pemaknaan aktor terhadap simbol-simbol tertentu. Wawancara banyak
dipergunakan untuk lebih memahami konteks sosial budaya dan politik yang melingkupi
setiap aktor dalam mengonstruksi ke-Mentawai-an, sehingga dapat menghasilkan
‘pendeskripsian yang kental’ sebagaimana dikembangkan oleh Geertz (1973) yang biasa
digunakan dalam penelitian-penelitian antropologis. Untuk memandu wawancara tersebut di
lapangan, sebelum turun ke lapangan pedoman wawancara telah dipersiapkan.
Selama di lapangan, penulis hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan
oleh LSM Citra Mandiri di Siberut. Dalam pertemuan itu, hadir juga anggota Dewan Adat
yang difasilitasi oleh LSM Citra Mandiri. Perbincangan dengan mereka lebih difokuskan
pada persoalan bagaimana agar Dewan Adat yang telah dibentuk oleh para aktivis LSM di
Siberut diakui keberadaannya oleh masyarakat. Meskipun pada saat pertemuan anggota LSM
berusaha untuk selalu menggunakan kata laggai untuk menyebut desa, namun anggota
Dewan Adat yang hadir sama sekali tidak menggunakan kata tersebut.
Berkaitan dengan perbincangan peraturan laggai, selain dari mereka yang tergabung
dalam anggota Dewan Adat (punutubut uma), para kerei dan sikebbukat uma juga
diwawancarai sebagai informan yang dikategorikan sebagai elit budaya yang memiliki
pengetahuan tentang nilai-nilai budaya Mentawai. Wawancara juga dilakukan dengan para
pelajar dan mahasiswa Mentawai yang sudah dan sedang menjalani studi di Padang. Anggota
organisasi dan LSM juga diwawancarai dengan pertimbangan, mereka merupakan para elit
terpelajar Mentawai, sebagai kelompok Simasoppit (cendekia). Banyak dari mereka yang
tergabung dalam organisasi-organisasi dan LSM saat penelitian ini, sebagian mereka terlibat
aktif dalam memunculkan konsep laggai.
Semua nama informan dan nama orang yang diceritakan dalam tulisan ini disamarkan,
kecuali yang dikutip dari sumber tertulis dan nama tokoh yang tidak mungkin disamarkan.
Cara ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pihak-pihak yang dapat
merugikan informan, orang lain yang terkait serta peneliti sendiri. Oleh karena informannya
35
hampir dari semua kalangan, orang tua dan pemuda, laki-laki dan perempuan, yang sudah
menikah dan yang belum. Untuk laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai anak serta
duda dalam tulisan ini disebut Aman dan diikuti nama samarannya. Untuk perempuan yang
sudah mempunyai anak, termasuk janda dalam tulisan ini disebut Inan dan diikuti nama
samarannya. Oleh karena menggunakan sebutan lokal yang umum dipakai di barasi
penelitian, maka Aman dan Inan ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk nama-nama
informan Mentawai tanpa sebutan Aman dan Inan menunjukkan bahwa mereka belum
menikah, untuk yang perempuan mereka masuk kategori Siokkok dan yang laki-laki masuk
kategori Silainge.
F. 3. Analisis Data
Menurut Philips dan Jőrgensen (2007: 1), tidak ada konsensus yang tunggal atas makna
wacana dan juga langkah-langkah untuk menganalisisnya. Namun demikian, dalam studi ini
orang berwacana dapat dipahami sebagai bentuk usaha pengonstruksian identitas dan
sebaliknya orang pun mengonstruksi identitas dalam wacana. Pengumpulan data dimulai
dengan berbagai pernyataan, ungkapan dan mengamati tindakan yang terkait dengan wacana
identitas dalam kehidupan sehari-hari di Barasi Muntei. Adapun data-data dari hasil
wawancara dan pengamatan (observasi) dicatat dengan cermat dan rinci menjadi suatu field
notes yang kemudian dianalisa. Semua data hasil pembacaan teks-teks media secara seksama
dicatat untuk menemukan hubungan di antara statement-statement tertulis yang dimunculkan
berkaitan dengan penolakan Perda Nagari dan pengusungan laggai. Pembacaan teks-teks
dengan seksama dilakukan untuk menemukan hubungan antara isu-isu atau tema menonjol
yang dimunculkan di media (Pualiggoubat) dan alasan mengapa media ini yang dipilih oleh
pewacana. Selanjutnya, hal tersebut dilihat dalam hubungannya dengan formasi diskursif
yang dibentuk dalam membangun wacana tentang ke-Mentawai-an.
Melalui data yang diperoleh, ditemukan keterkaitan hubungan kekuatan-kekuatan yang
turut memainkan peran dalam proses pembentukan wacana ke-Mentawai-an. Berangkat dari
pemahaman-pemahaman itu, penulis menjabarkan analisis bagaimana proses tersebut
mengambil bentuk-bentuk (pada ruang dan waktu) yang konkret dan keterlibatan aktor yang
bermain di dalamnya, serta bagaimana wacana ke-Mentawai-an itu diperbincangkan,
dimaknai kembali dan diperdebatkan. Dalam hal ini, bagaimana aktor menginterpretasi dan
memaknai simbol-simbol serta tanda-tanda yang berkembang dan hadir di hadapannya,
semua diinterpretasikan melalui data-data yang diperoleh. Selain itu, cara pandang
(interpretasi) aktor dalam pewacanaan identitas (ke-Mentawai-an) dalam konteks kekinian,
36
pemahaman tentang kondisi sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhinya, saling
dihubungkan satu sama lainnya.
Gagasan-gagasan, ide-ide, terminologi, konsepsi, pemaknaan tentang ke-Mentawai-an
dan berbagai praktik sosial menjadi sasaran analisis. Data-data primer dari hasil pengamatan
dan wawancara mendalam serta data sekunder dari literatur dan media massa sebagaimana
dipaparkan di atas dianalisa secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan. Hasilnya disajikan
berupa deskripsi etnografi, karena tulisan antropologi berupa etnografi pada dasarnya tidak
lebih dari suatu bentuk wacana kebudayaan (Alam, 1998:6).
G.
Jalannya Penelitian, Kendala dan Hal-hal yang Mendukung
Penelitian disertasi ini secara lebih intensif dimulai pada bulan Oktober 2007 sampai
dengan awal Mai 2008. Selama penelitian, penulis berusaha terlibat secara langsung dalam
berbagai aktivitas subjek yang diteliti, melakukan wawancara mendalam dan menyimak
obrolan-obrolan di tempat-tempat umum dan ‘gosip-gosip’ yang berkembang, merupakan
data yang diperoleh secara tidak sengaja, namun data ini sangat penting. Selain itu, penulis
ikut serta ke ladang-ladang penduduk, bekerja bersama dalam pekerjaan-pekerjaan
perempuan, seperti mencari ikan, ulat sagu, sayur, bambu (okbug) untuk memasak, kayu
bakar, mengolah sagu dengan tangan (pasibutcit sagu), menganyam atap dari daun sagu
(tobat), serta mencuci dan mandi di sungai.
Beberapa pekerjaan laki-laki yang diamati dan diikuti saat penelitian antara lain:
menebang sagu, memotong kayu di hutan, mengolah sagu, mencari rotan, mengambil
bambu, menyuling minyak nilam, memberi makan babi, membersihkan ladang pisang,
ladang kakao dan memetik buah kakao. Tidak untuk semua tahap pekerjaan laki-laki penulis
dapat terlibat, misalnya: tidak ikut menebang sagu, tapi ikut mengolah sagu dengan cara
‘pasideret akhek sagu’ (menginjak-injak sagu) yang sebenarnya tidak lazim dilakukan
perempuan. Ikut membantu membawa kepingan batang sagu, mencincang-cincangnya
sampai menjadi serpihan yang siap diolah di tempat pengolahan. Penulis tidak ikut
memotong kayu dengan sinso (chainsaw), tetapi ikut mengangkat lempengan kayu ke atas
sampan.
Selama penelitian berlangsung, penulis masih menghadapi kendala dalam bahasa.
Harus diakui bahwa perbedaan dialek pun menjadi kendala tersendiri. Meskipun beberapa
orang Mentawai menganggap penulis bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, tetapi
37
peneliti lebih memahami Dialek Sarereiket dibanding Dialek Sabirut. Jika harus melakukan
wawancara dengan orang yang berusia di atas 50 tahun dan mereka menggunakan Dialek
Sabirut, penulis masih merasa kesulitan. Untuk itu, penulis selalu ditemani oleh orang
Mentawai yang lebih muda dan lancar berbahasa Indonesia. Sementara untuk mewawancarai
mereka yang masih muda tidak banyak kendala, karena umumnya mereka mengerti dan
lancar menggunakan Bahasa Indonesia, terutama kaum laki-laki. Kaum perempuan muda
pun cukup banyak yang memahami Bahasa Indonesia dan Bahasa Minangkabau.
Keuntungan lain banyak kaum muda, terutama yang sudah bersekolah, dalam pergaulan
sehari-hari di barasi pun lebih banyak menggunakan Bahasa Minangkabau.
Kesulitan-kesulitan di lapangan banyak mempengaruhi jalannya penelitian, dan yang
cukup ‘mengganggu’ adalah masalah makanan, terutama babi. Meskipun pada kunjungankunjungan ke Mentawai sebelumnya, saya sudah sering makan bersama dengan mereka yang
mengonsumsi babi, tetapi selalu saja terasa berat di awal-awal memulai tinggal bersama
mereka. Saya harus membiasakan diri lagi berada dan makan bersama dengan orang-orang
yang mengonsumsi babi, hanya saja ‘emosi keagamaan’ sering mengganggu jalannya
penelitian ini. Saya sadar jika tidak mau makan babi akan membuat orang Mentawai
memandang penulis sasareu yang patut dicurigai, sasareu yang menganggap orang
Mentawai 'kotor', sasareu yang ‘merendahkan’ orang Mentawai karena orang Mentawai
makan babi. Ini berpengaruh terhadap kebutuhan informasi yang ingin diperoleh. Untuk itu,
walaupun tidak mengonsumsi babi dengan memberikan alasan bahwa saya tidak suka makan
daging, tetapi mencoba meminimalisir ‘kecurigaan’ itu dengan cara ikut bersama memasak
babi. Selain itu, saya ikut makan ulat sagu yang dianggap makanan ‘kotor’ atau ‘rendah’ oleh
Sasareu sebagai ‘strategi merendahkan diri’ (dalam istilahnya Bourdieu) di depan orangorang Mentawai di barasi. Saya menjadi terbiasa makan sagu, keladi, ubi kayu, dan pisang
sebagai makanan pokok sehari-hari. Sesekali saya juga makan nasi jika keluarga-keluarga
yang ditumpangi makan nasi. Kadangkala peneliti turut membeli beras untuk dimakan
bersama keluarga yang ditumpangi.
Pengalaman lain yang dihadapi selama penelitian dan cukup mengganggu ialah ketika
penulis sakit dan diobati oleh kerei, karena setelah empat bulan di lokasi, tubuh panas dan
mual-mual. Saya dianjurkan Aman Jupin, seorang laki-laki Sarereiket untuk berobat pada
sasarainanya27 yang juga seorang kerei di barasi tetangga. Setelah sampai di rumah kerei
27
Kerabat dari garis ibu dan kadangkala orang Mentawai mengatakan bahwa sasaraina artinya sama dengan
dunsanak dalam bahasa Minangkabau.
38
tersebut saya diminta berbaring di lantai kamar, kemudian perut dipegang oleh kerei itu
untuk mendiagnosa penyakit. Kerei itu mengatakan kalau sakit yang saya rasakan
disebabkan saya sedang ‘hamil’. Meskipun sangat kaget dengan pernyataan kerei itu, tetapi
saya
tidak membantahnya. Ketika ditanya siapa ‘ayah’ bayi yang dikandung, saya
mengatakan kalau ‘ayah’ bayi yang ‘dikandung’ adalah suami saya yang pada saat itu tidak
berada di lokasi penelitian.
Mendengar jawaban saya, kerei itu langsung mengatakan tidak mungkin suami saya
yang tidak sedang berada di barasi yang ‘menghamili’, karena sudah hampir empat bulan
saya di Siberut, sementara menurut kerei usia kehamilan itu baru dua bulan lebih. Dia terus
mendesak untuk memberitahukan siapa ‘sebenarnya’ yang telah membuat saya ‘hamil’.
Jawaban saya yang tidak pernah berubah membuat kerei itu pun 'tidak mau percaya’.
Ketidakpercayaannya
itu
membuat
dia
mengajukan
pertanyaan
yang
semakin
membingungkan dan sekaligus membuat saya takut, karena dia menanyakan apakah
‘kandungan itu akan digugurkan'. Saya menolak untuk melakukannya, tetapi kerei itu tidak
menjawab langsung dan malah meminta saya untuk tidur dulu di kamar itu dan memikirkan
lagi keputusan itu baik-baik.
Sampai sore berada di rumah kerei itu dan setiap kali ditanya, saya tetap mengatakan
padanya kalau kandungan itu tidak akan digugurkan. Akhirnya saya dimantrai dengan
beberapa tumbuhan, minum air tebu dan sari pati umbi-umbian dan daun-daunan yang
diambil di pekarangan rumahnya. Ampas daun-daunan yang digunakannya untuk ramuan
obat dibalurkan ke perut, tangan, kaki dan kepala saya. Ada rasa takut dalam diri saya pada
saat disuruh minum ramuan yang sudah disiapkan, tetapi tetap saja diminum. Kemudian
selama seminggu kulit saya dipenuhi bintil-bintil berwarna merah dan terasa gatal, terutama
di bagian perut.
Diagnosa kerei mengenai ‘kehamilan’ itu cukup mengganggu karena saya merasa
orang di barasi mempergunjingkan 'kehamilan' yang bukan dari hasil hubungan dengan
suami yang sah. Itu berarti saya sudah ‘berselingkuh’ dengan orang lain di barasi. Cerita
tentang perselingkuhan beberapa orang warga barasi sudah sering terdengar dan biasanya
menjadi ‘topik’ pergunjingan yang hangat di antara kaum perempuan, juga di antara kaum
laki-laki. Sekalipun saya icoba untuk tidak memikirkannya karena merasa yakin saya tidak
hamil dan tidak 'berselingkuh', tetapi beban psikis ini tetap dirasakan sampai saya
meninggalkan lokasi penelitian.
39
Kesulitan lain yang dihadapi adalah setiap melihat keluarga yang ditumpangi makan
babi bersama, suasana yang penuh kegembiraan berubah menjadi diam karena sering
kehadiran saya menjadi penyebab mereka berhenti makan. Saya jadi bertanya pada diri
sendiri, haruskah kegembiraan, kebersamaan, kenikmatan mereka makan babi bersama
terusik oleh kehadiran saya di rumah mereka sebagai ‘pendatang’ atau ‘the Other’? Haruskah
saya menghindar terus, karena merasa ‘terganggu’ pada saat melihat orang-orang yang saya
amati makan babi karena keyakinan yang saya anut? Siapa sebenarnya yang menjadi
‘pengganggu’ dalam hubungan saya (peneliti) dan orang Mentawai, kebiasaan mereka makan
babi itukah atau pikiran saya tentang babi itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu ikut ambil
bagian dalam peran yang dijalani sebagai ‘the Other-nya’ orang Mentawai selama penelitian.
Pengalaman-pengalaman lain di lapangan, tinggal bersama keluarga-keluarga
Mentawai di barasi atau di ladang-ladang sering kali memberikan tantangan tersendiri. Saya
sering dihadapkan pada pilihan yang sulit pada saat melakukan penelitian ini. Di satu sisi,
saya adalah seorang Sasareu yang berupaya untuk ‘menjadi’ Simattawai, tetapi sudah tentu
saya tidak bisa menjadi Simattawai yang sesungguhnya sekalipun sudah mencoba untuk
terlibat dalam berbagai kegiatan dan mengikuti cara-cara hidup mereka. Sebagai peneliti dan
sekaligus juga seorang Sasareu yang memerlukan informasi dan data yang ‘nyata’ di
lapangan, mendorong saya untuk ‘berpura-pura’ menjadi Simattawai dengan alasan akan
lebih menyulitkan apabila bertindak sebagai seorang yang ‘murni’ Sasareu sehingga benarbenar ‘dicap’ Sasareu oleh Simattawai.
Kepura-puraan itu menjadi bagian dari tindakan-tindakan ‘politis’ yang dilakukan
terkait dengan ‘interest’ saya sebagai peneliti. Tidak tahu bagaimana orang Mentawai
‘memandang’ saya, khususnya mereka yang tinggal di Barasi Muntei. Kadang mereka
mengatakan saya sudah menjadi seorang ‘Mentawai’, tetapi tetap ‘dicurigai’ karena saya
memang ‘Sasareu’. Kecurigaan itu salah satunya disampaikan langsung kepada saya oleh
Aman Pius, seorang kerei. Pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pandangan orang
Mentawai Siberut terhadap saya dan kecurigaan mereka bisa ditemukan pada paparan babbab selanjutnya dalam tulisan ini.
Selain dari kendala-kendala tersebut di atas, juga ada hal-hal yang mendukung saat
penelitian ini dilaksanakan. Ada dua hal menurut saya yang cukup mendukung jalannya
penelitian ini. Pertama, penelitian ini dilakukan pada saat penolakan penerapan Perda No. 2
Tahun 2007 tentang pemberlakuan ‘nagari’ di seluruh Sumatera Barat, termasuk Mentawai.
Kedua, penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama dengan penelitian sebelumnya. Berarti
40
hubungan pertemanan sudah dibangun sebelumnya sehingga lebih memudahkan penulis
untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat, setidaknya dengan warga Barasi Muntei.
Beberapa warga barasi tetangga lain juga, karena sudah saling mengenal sebelumnya.
Keberuntungan lain adalah selama penelitian beberapa uma ‘kebetulan’ mengadakan ritual
yang berkaitan dengan Arat Sabulungan sehingga ritual-ritual tersebut bukanlah
ritual
‘pesanan’.
H. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian ini disajikan dalam tulisan yang terbagi dalam beberapa bab. Bab I
merupakan pengantar pada persoalan penelitian berisi alasan mengapa kajian ini penting dan
bagaimana kajian-kajian yang sudah dilakukan berkaitan dengan persoalan konstruksi
identitas orang Mentawai. Bab II berisi tentang deskripsi etnografis dalam kaitannya dengan
identitas Mentawai secara umum, terutama di Barasi Muntei yang menjadi fokus studi
pengonstruksian ke-Mentawai-an. Bab III memuat tentang pengonstruksian identitas orang
Mentawai dalam mitos. Melalui pemaparan mitos kita dapat melihat bangunan diskursif
identitas Mentawai yang sudah ada sebelumnya. Selain itu konteks historis relasi orang
Mentawai dengan orang luar (Sasareu) yang dimulai dari masuknya orang asing ke
Mentawai yang memberikan informasi tertulis mengenai kehidupan orang Mentawai, dan
hubungannya dengan Sasareu terutama dengan orang Minangkabau sebagai pendatang yang
dominan di Mentawai. Bab IV mengupas hubungan wacana identitas orang Mentawai
dengan isu-isu nasional maupun internasional, secara spesifik mengenai hubungan
kemunculan kaum cendekia (Simasoppit) Mentawai sebagai kelompok elit yang aktif
menyuarakan perlawanan terhadap orang Minangkabau. Selain itu, mengenai penetapan
model sistem administrasi pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, karena dianggap sebagai
identitas yang berlawanan, sehingga melahirkan ide pemerintahan Laggai. Bab V berisi
tentang pertarungan wacana dalam perbincangan laggai sebagai bagian dari pengonstuksian
ke-Mentawai-an yang menunjukkan identitas Mentawai bukanlah suatu yang tunggal dan
dalam bangunan wacana yang berbeda. Perbedaan itu semakin terlihat dengan dua pilihan
nama pengganti desa, yakni Pulaggajat atau Laggai. Bab VI menghadirkan ulasan dan
analisis mengenai kesejajaran dan kesenjangan antara wacana identitas Mentawai dengan
praktik kehidupan sosial sehari-hari orang Mentawai di Barasi Muntei. Bab VII berisi
kesimpulan yang merangkum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian beserta
implikasi teoritis dan praktis.
41