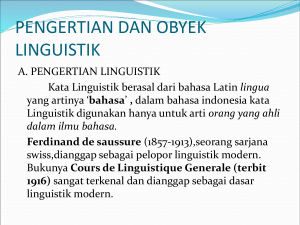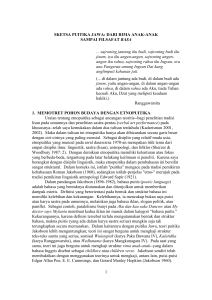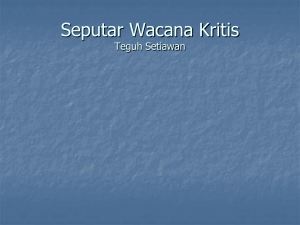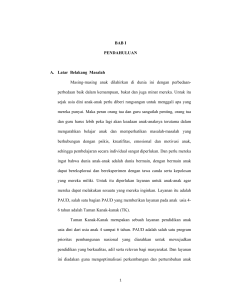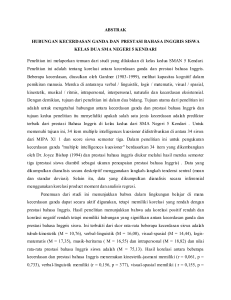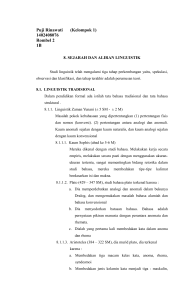BERKENALAN DENGAN ETNOPUITIKA Abstract
advertisement

BERKENALAN DENGAN ETNOPUITIKA Abstract: This paper presents ethnopoetics from the linguistic perspective by making the best use of structural approach. Ethnopoetics is essentially the study of poetic or verbal art performance; it tries to understand the nature and structure of poetic performance as situated in its local context. Toward this end, ethnopoetics relies heavily on Jakobson s linguistic poetics on the one hand and on literary poetics on the other, while using local knowledge to shed light on a given poetic performance to reveal its literary as well as its ritual significance. To show the working mechanism of ethnopoetics, the paper looks critically at Hymes s and Tedlock s models, unraveling their respective strengths and weaknesses. As a theoretical framework for investigating verbal art performance, ethnopoetics as introduced in this paper should help enrich the research in oral tradition in Indonesia. Key words: ethnopoetics, linguistic poetics, local knowledge, Hymes s model, Tedlock s model, oral tradition. 1. DARI PUITIKA KE ETNOPUITIKA Istilah puitika telah lama dikenal di dunia sastra; dan puitika Aristoteles, yang dikemukakan sebagai pasangan retorika, lazimnya dianggap sebagai rujukan puitika yang tertua (periksa, misalnya, Todorov 1981, dan Russel & Winterbottom 1998). Dalam pemikiran sastra modern, nampaknya Jonathan Culler-lah (1975; 1997) yang paling serius menggarap bidang ini, dan mengemukakan puitika sebagai sebuah teori sastra, yang terutama bermaksud mempelajari literary comptence. Istilah yang terakhir ini mendekatkan puitika sastra dengan linguistik, bukan pada tahap metode atau analisisnya tetapi pada tahap pemikiran teoritisnya. Karya Culler Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature (1975) adalah sebuah tesis yang relatif baru, yang banyak diilhami oleh teori linguistik (yang dikemukakan oleh Saussure dan Chomsky) dan juga oleh puitika linguistik (yang dikemukakan oleh Jakobson). Hubungan itu nampak jelas, antara lain, dari istilah yang digunakan oleh Culler, yaitu literary competence di bidang sastra, yang merupakan counterpart bagi istilah yang dipopulerkan oleh Chomsky, yakni linguistic competence di bidang linguistik. Ditinjau dari sudut pandang linguistik, puitika bisa memiliki arti sempit dan luas.1 Dalam pengertiannya yang sempit, puitika termasuk bagian dari linguistik terapan atau applied linguistics. Di sini, puitika berarti penerapan metode dan teknik analisis linguistik terhadap teks sastra, terutama puisi (Crystal 1991). Analisis teks puisi dengan model ini banyak dilakukan oleh para ahli bahasa yang mencintai sastra (dan juga oleh sejumlah ahli sastra yang menguasai linguistik), sejak akhir masa kejayaan aliran Strukturalisme pascaBloomfield sampai dengan muncul dan berkibarnya aliran Linguistik Generatif ala 1 Puitika linguistik ini telah saya bahas dalam sebuah artikel berjudul Puitika Linguistik: Antara Kejernihan Struktur dan Kabur Makna , yang dimuat dalam jurnal Bahasa dan Seni, terbitan Februari 2001, hlm. 1-22. Dalam makalah untuk Semiloka ATL ini saya menyarikan kembali secara kritis apa yang telah saya tulis dalam artikel tersebut, meskipun tetap ada tumpang-tindih yang tak terhindarkan. Chomsky (periksa, misalnya, Allen 1964, Hill 1969, Haugen & Bloomfield 1973, dan Newmeyer 1983).2 Dalam pengertiannya yang luas, puitika linguistik lazimnya mengacu pada makalah Jakobson, yang kini dipandang sebagai sebuah karya klasik, yaitu Linguistics and Poetics (1960 [1987]). Menurut Jakobson, bahasa memiliki berbagai fungsi, yang salah satunya adalah fungsi puitis atau poetic function. Menurut definisi formalnya, the poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination (1960 [1987]: 71). Yang dimaksud dengan the axis of selection adalah poros paradigmatik, yang dapat dibayangkan sebagai daftar atau lajur-menurun dari kosakata dalam mental lexicon kita. Sedangkan the axis of combination atau poros sintagmatik adalah lajur-mendatar, di mana sejumlah kosakata dapat disusun menjadi frasa atau kalimat puitis menurut kaidah-kaidah sintaksis. Bahkan, untuk menghasilkan bahasa puitis, seorang penyair dapat pula dengan sengaja memperkosa kaidah-kaidah sintaksis.3 Jadi, the principle of equivalence atau prinsip keseimbangan itulah yang menentukan pemilihan (kata, rima, makna, dsb.) pada poros paradigmatik untuk kemudian diproyeksikan pada poros sintagmatik, sehingga menghasilkan bahasa puitis atau poetic language. Perlu dicatat bahwa istilah bahasa puitis ala Jakobson tidak hanya meliputi bahasa puisi atau teks sastra, tetapi juga semua jenis bahasa yang dibentuk berdasarkan prinsip keseimbangan tersebut. Contoh paling terkenal dari puitika Jakobson adalah I like Ike, sebuah slogan politik di Amerika Serikat pada tahun 1950-an yang menjagokan Eisenhower sebagai presiden. Pada akhirnya, pemilihan presiden itu memang dimenangi oleh Ike atau Dwight Ike Eisenhower. Jakobson sendiri memuji bagusnya slogan kampanye kepresidenan I like Ike tersebut. The [...] poetic function of this campaign slogan reinforces its impressiveness and efficacy (1960 [1987]: 70). Sebagaimana ditandaskan ulang oleh Culler (1997: 30), Here, through word play, the object liked (Ike) and the liking subject (I) are both enveloped in the act (like): how could I not like Ike, when I [ay] and Ike [ayk] are both contained in like [layk]? (lambang fonetik ditambahkan). Seandainya Jakobson masih ada di antara kita, dan dia menguasai bahasa Indonesia dengan baik, apakah dia juga akan memberikan pujian yang sama terhadap, misalnya, kalimat iklan Jamu manjur cap air mancur atau Aku dan kau suka Dancow ? Kemungkinan besar, jawabannya adalah ya . Mengapa? Karena, jika dianalisis secara struktural, kedua iklan komersial tersebut memiliki struktur yang mirip bagusnya dengan I like Ike. Menghadapi kasus semacam ini, tentunya ahli sastra keberatan untuk sepenuhnya menerima puitika Jakobson, karena teorinya mencampuradukkan antara kecantikan bentuk dan keindahan makna. Maksudnya, struktur yang cantik , misalnya yang terdapat dalam slogan politik atau bahasa iklan, belum tentu berisi makna yang indah dalam pengertian sastra. Artinya, di sini bahasawan (yang secara gamblang menegaskan bahwa 2 Saya, yang belum sempat mempelajari aliran-aliran ilmu bahasa yang berkembang di Eropa dan Australia, hanya pernah tahu secara selentingan bahwa tokoh-tokoh seperti Widdowson, Halliday, dan Hassan juga menerapkan metode linguistik untuk menganalisis teks sastra. 2 Contoh pemerkosaan kaidah-kaidah sintaksis dalam penciptaan puisi nampak, misalnya, pada beberapa karya penyair Amerika E. E.. Cummings. Sebagai ilustrasi terbaik, menurut pendapat saya, adalah puisinya yang berjudul Anyone Lived in a Pretty How Town , yang bait pertamanya adalah sebagai berikut. anyone lived in a pretty how town (with up so floating many bells down) spring summer autumn winter he sang his didn t he danced hid did. bahasa puitis juga merupakan obyek formal bagi penelitian linguistik) terjebak dalam kesulitan tentang bagaimana menemukan makna puitis melalui analisis struktural. Maksudnya, bahasawan, dengan menggunakan pisau analisisnya, mencoba membedah struktur poetic language untuk menemukan dan sekaligus menjelaskan poetic meaning yang terkandung di dalamnya. Namun, yang sering terjadi adalah seperti seseorang yang mengupas bawang: lapis demi lapis, atau kelopak demi kelopak, dan pada akhirnya ia hanya menemukan kosong dan sepi . Secara metodologis, Jakobson, yang mengembangkan dan menyempurnakan tradisi formalisme Rusia, tidak salah. Karena memang demikianlah seharusnya linguistik bergerak dari kulit menuju isi, atau dari bunyi menuju makna. Sebagaimana dikatakan oleh Harris (1995), The most frequently invoked definition of linguistics [...] calls language a path running from sound to meaning, and calls linguistics the exploration of that path (hlm. 12). Bagaimana bahasawan mengatasi kesulitan di atas? Ada yang menyarankan agar kita mengikuti saran Derrida, yang mengatakan bahwa, Ordinary language tells, but poetic language shows . Artinya, bahasa puitis bukan hanya berfungsi sebagai saranakomunikasi-verbal pembungkus-makna, tetapi ia hadir sebagai totalitas bahasa yang hidup dengan ruhnya sendiri. Ia bisa hadir untuk menggelitik, mengejek, memecah, merobek, atau mendobrak. Ia adalah suara hati-nurani yang sedang menyapa hati-nurani yang lain. In a poem, each word, being equally important, exists in absolute focus [...]. In a poem, [words] are actions , kata Strand (1991: xiv). Pada batas inilah, bahasawan yang menghadapi bahasa puitis menjadi termangumangu. Ia bisa tergoda untuk memulai analisisnya dari makna puitis, kemudian bergerak menuju bentuk atau struktur. Tetapi, bila metode ini ditempuh, ia bisa kehilangan arah. Karena, makna puitis, meminjam kata-kata Goenaman Mohamad, adalah arah singgah yang penuh penjuru . Ungkapan ini mengingatkan kita pada buku Harris (1995) The Linguistics Wars. Buku ini memberikan uraian secara mendalam, tajam, dan sering kali satir terhadap peperangan antara kubu Chomsky (kaum semantik interpretif) dan kubu Lakoff (kaum semantik generatif). Dua aliran yang sama-sama bersumber dari Linguistik Generatif (yang dipelopori oleh Chomsky sejak akhir dasawarsa 1950-an) ini tak pernah menemukan titik temu: Di mana makna harus diletakkan dalam teori atau analisis kebahasaan? Kaum semantik interpretif berpendapat bahwa panglima linguistik adalah sintaksis, dan cabang-cabang lainnya (fonologi, morfologi, dan semantik) cukup berpangkat prajurit saja. Sedangkan menururt pandangan kaum semantik generatif, sang raja adalah semantik atau makna, dan yang lain-lainnya cukup menjadi pelayannya saja. Pada akhirnya, dari linguistics wars yang berlangsung selama dasawarsa 1970-an tersebut, Chomsky dan para pengikutnya keluar sebagai pemenang. Artinya, dalam Linguistik Generatif, makna atau semantik tetap menempati kedudukan periferal, dan tak pernah diberi kesempatan untuk berada pada kedudukan sentral. Makalah ini hanya bermaksud menunjukkan bahwa linguistik, baik yang menggunakan pendekatan formal (misalnya ala Chomsky) ataupun pendekatan yang lebih humanistik (misalnya ala Hymes atau Halliday), hanya dapat memberikan analisis struktural dan penjelasan parsial, terutama terhadap misteri makna dalam bahasa puitis. Meminjam istilah Chomsky, di hadapan bahasa puitis, linguistik hanya dapat melakukan sebagian saja dari descriptive adequacy (ketuntasan pemerian), dan rasanya mustahil untuk bisa sampai pada explanatory adequacy (ketuntasan penjelasan). Jadi, memang harus ada division of labor antara linguistik dan sastra. Pada aspek struktur, the explanatory power of linguistics, baik pada tingkat mikro (core linguistics) ataupun makro ( hyphenated linguistics), memang mengalami kemajuan yang manakjubkan.4 Namun, tetap harus diakui bahwa dalam menghadapi bahasa puitis atau teks sastra, linguistik, sebagai acuan teoritis dan pisau analisis, memiliki kelebihan dan sekaligus keterbatasannya. Dari uraian singkat mengenai puitika linguistik di atas, ada satu persamaan yang dapat ditarik, yang akan mengarahkan pembicaraan kita pada etnopuitika. Yaitu, analisis linguistik terhadap bahasa puitis atau teks sastra, baik yang menggunakan metode Jakobson yang bersifat total maupun yang menggunakan teknik analisis linguistik terapan yang bersifat parsial, keduanya belum menyentuh verbal art performance atau pentas sastra . Artinya, aspek bunyi dari bahasa puitis, atau lebih tepatnya the art of sounding literary texts, belum disentuh oleh penelitian kebahasaan di atas. Berikut ini diperkenalkan secara ringkas: binatang apakah itu yang disebut dengan etnopuitika. 2. ETNOPUITIKA DUNIA LOKAL DAN PENTAS SASTRA Sebagai penyambung uraian yang mengaitkan puitika dengan etnopuitika di atas, ada baiknya bagian ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana (dan mungkin terdengar agak tolol): Mengapa para siswa SD atau SLTP selalu mendeklamasi-kan sajak atau puisi, tetapi tidak pernah mendeklamasikan, umpamanya, surat undangan atau teks pengumuman? Jawabannya, karena hanya teks sastralah yang layak dideklamasikan atau dipentaskan. Telah sering kita dengar orang mengutip penyair Inggris Alexander Pope, The sound must seem an echo to the sense . Penyair Amerika Longfellow, dalam bait kesebelas dari sajaknya The Day is Done (yang terdiri dari 12 bait) itu, juga menyarankan hal serupa, Then read from the treasured volume / The poem of thy choice / And lend to the rhyme of the poet / The beauty of thy voice . Menyimak saran Longfellow ini, kita setuju bahwa the beauty of thy voice dalam membaca sebuah sajak ditentukan terutama oleh the rhyme of the poet. Dengan kata lain, di dalam teks sastra, terutama puisi, terkandung nada yang secara alami menyarankan agar pembaca menyuarakan puisi tersebut, untuk mendapatkan maknanya yang penuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Hunter (1991: 190), yang menyatakan, Poetry is, almost always, a vocal art, dependent on the human voice to become its full self [...]. In a sense, it begins to exist as a real phenomenon when a reader reads and actualizes it. Poems don t really achieve their full meaning when they merely exist on a page; a poem on a page is more a score or set of stage directions for a poem than a poem itself. Kedekatan antara bentuk dan makna atau iconicity, sebagaimana yang disarankan oleh Pope dalam ungkapan the sound must seem an echo to the sense di atas, membantu menciptakan nada bagi puisi atau bahasa puitis pada umumnya. Jadi, puisi memang ingin menjadikan dirinya iconic, dan secara sengaja melanggar salah satu kaidah kebahasaan yang menyatakan bahwa hubungan antara bentuk dan makna pada umumnya bersifat arbitrary . Dan sifat iconic dari bahasa puitis atau teks sastra terdengar semakin jelas dan menonjol bila ia dilisankan atau dipentaskan. Pada aspek tekstual inilah terdapat kesejajaran antara puitika dan etnopuitika: bahasa puitis adalah bahasa yang lazim dan enak dipentaskan. Perbedaannya adalah, dalam etnopuitika, perhatian terhadap pentas sastra dan warna budaya lokal selalu ditekankan. 4 Dalam ilmu bahasa, linguistik mikro atau core linguistics meliputi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan linguistik makro, yang terkadang disebut juga hyphenated linguistics , meliputi pragmatik, sosisolinguistik, linguistik antroplogi, psikolinguistik, etnolinguistik, neurolinguistik, dsb. Sementara istilah puitika berakar pada Aristoteles dan berasal dari masa lebih dari dua milenium yang lalu, istilah etnopuitika diperkenalkan ke dunia akademis baru beberapa dasawarsa yang lalu. Tepatnya etnopuitika diperkenalkan oleh Rothenberg pada tahun 1968, melalui jurnal Alcheringa. Jurnal ini kemudian hanya terbit beberapa kali, dan kemudian lenyap dari percaturan dunia sastra dan linguistik.5 Demikian pula nama Rothenberg; ia tergeser oleh tokoh-tokoh yang lebih mapan di bidang etnopuitika, seperti diurutkan secara alfabetis Bauman, Briggs, Hymes, Sherzer, Tedlock, dan Woodbury. Tergesernya Rothenberg tersebut kemungkinan disebabkan oleh sikapnya yang terlalu nyentrik dan permisif. Dia nyentrik, karena kesenimanannya (atau kepenyairannya) lebih menonjol daripada sikapnya sebagai ilmuwan; dan dia permisif, karena membolehkan hampir apa saja memasuki bidang studi etnopuitika. Akibatnya, etnoputika ala Rothenberg menjadi kehilangan fokus dan arah yang jelas. Dalam perkembangan selanjutnya, ada dua ciri utama yang secara khas menandai etnopuitika. Pertama, etnopuitika memfokuskan diri pada pentas sastra atau verbal art performance. Dalam hal ini etnoputika dapat dipandang sebagai puitika-pentas , yang merupakan titik temu dari berbagai disiplin, seperti linguistik, antroplogi, sastra (lisan), dan folklore (Sherzer & Woodbury 1987: 2). Kedua, etnoputika berusaha mempelajari makna pentas sastra serta implikasinya dengan lebih dahulu memahami pengetahuan lokal. Artinya, setiap kelompok budaya (a culture) atau komunitas penutur bahasa (a speech community) memiliki ciri-ciri lokal yang khas, yang tidak terdapat pada kelompok budaya atau komunitas penutur bahasa lainnya. Ciri-ciri khas tersebut harus dikenal secara baik oleh peneliti bila ia berharap untuk dapat memberikan deskripsi yang memadai (adequate description) terhadap penelitiannya di bidang etnopuitika. Singkatnya, etnopuitika adalah puitika-pentas yang bercirikan budaya lokal. Sebagai contoh, Florida (1987) tidak sepenuhnya salah ketika secara agak arogan dia menulis makalah Reading the Unread of Javanese Literature . Kenyataannya memang orang Jawa moderen, lebih-lebih angkatan mudanya, banyak yang merasa berhadapan dengan bahasa asing ketika menghadapi naskah-naskah klasik, seperti Wulangreh, Kalatidha, Tripama, atau Wedhatama. Apalagi jika naskah-naskah tersebut masih seperti aslinya, tertulis dengan huruf Jawa. Artinya, yang sudah ditransliterasikan ke dalam aksara Latin (Roman alphabet) pun masih tetap terbaca atau terdengar seperti bahasa asing . Sementara itu bagi angkatan tua , yang masih mampu membaca karya-karya adiluhung tersebut, makna yang terdapat dalam naskah-naskah klasik itu sering kali tidak terpahami secara tuntas.6 Jadi, ada benarnya bahwa Javanese 5 Yang dimaksudkan di sini terutama sastra lisan (karena etnopuitika lebih banyak berurusan dengan pentas sastra) dan linguistik humanistik (yang lebih dekat dengan humaniora daripada sain). Perlu diingat bahwa sejak munculnya aliran Strukturalisme Amerika, linguistics sering dinyatakan sebagai the mathematics of the language, sehingga ia dianggap lebih dekat dengan sain daripada humaniora. Tradisi linguistics is part of the natural science ini diteruskan oleh Linguistik Generatif, yang bahkan menjadikan linguistik lebih formal dan matematis. 6 Misalnya, saya sendiri merasa berhutang budi kepada Robson (1990), karena pemahaman saya terhadap Wedhatama menjadi lebih baik setelah membaca karyanya The Wedhatama: An English Translation. Bukubuku kecil seperti Wedhatama Jinarwa (Wedhatama yang Ditafsirkan), yang ditulis dalam bahasa Jawa, memang membantu orang Jawa moderen memahami makna Wedhatama. Namun, yang membuat karya Robson tersebut istimewa adalah pengantarnya. Dalam Introduction ini, Robson secara rinci menjelaskan kedudukan Wedhatama dalam sastra Jawa klasik, tingginya nilai sastra Wedhatama bagi masyarakat Jawa, lengkap dan padatnya isi Wedhatama mengenai falsafah hidup atau kebatinan Jawa, asal-usul naskah atau tinjauan filologis singkat terhadap teks Wedhatama, dan, yang terakhir, berbagai persoalan mengenai penerjemahan dan penafsiran Wedhatama (ke dalam bahasa Indonesia atau Inggris) dan bagaimana seharusnya penerjemah mengatasi masalah penerjemahan dan penafsiran tersebut. literature memang unread (by the Javanese). Pertanyaannya kemudian, tidak terbaca dalam arti bagaimana? Bila reading memang hanya diartikan sebagai reading comprehension dalam pengertian Barat, maka tesis Florida tersebut tidak meleset. Namun, pendapat yang Western-centric ini disanggah oleh Arps (1992). Bila orang Jawa menghadapi teks tembang atau sung-poetry, bisa terjadi dua hal. Pertama, ia dapat melakukan analytical reading, sebagaimana orang Barat melakukan reading comprehension. Atau, yang kedua, ia dapat melakukan poetic reading, dalam arti ia melagukan tembang tersebut terutama untuk dinikmati lagu atau bahkan misteri kandungan isinya daripada untuk dimengerti maknanya secara logis dan kritis.7 Dari kritik Arps terhadap Florida tersebut, apakah yang dapat kita simpulkan? Pemahaman pengetahuan lokal atau local knowledge merupakan prasyarat yang tak dapat ditinggalkan oleh peneliti di bidang etnopuitika.8 Dan hasil penelitian Arps mengenai tembang Jawa, yang dibukukan menjadi Tembang in Two Traditions: Performance and Interpretation of Javanese Literature, adalah sebuah contoh unggulan untuk penelitian etnopuitika. Hasil penelitian Arps ini juga memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap etnopuitika. Yaitu, teks sastra tidak harus hadir dan lahir melalui pentas. Dalam hal tembang performance, atau yang dalam istilah lokalnya dikenal sebagai macapatan, hampir dapat dipastikan bahwa teks selalu mendahului pentas . Perlu dicatat bahwa istilah teks di sini diartikan secara longgar, sebagai a stretch of verbal discourse. Jadi, teks bisa meliputi wacana lisan maupun tertulis. Jika yang ditekankan adalah pengertian teks tertulis , maka definisi formalnya menjadi an orthographic (or phonetic) record of the stretch of verbal discourse. Maksudnya, dalam berbagai penelitian sebelumnya, sering diyakini bahwa teks selalu hadir dan lahir melalui pentas. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli pentas atau verbal art performers yang tuna-aksara. Ini tidak berarti bahwa ahli pentas yang kenalaksara atau literate performers sekedar menghafal teks tertulis untuk kemudian dipentaskan. Sama sekali tidak demikian. Di negara tetangga kita, Malaysia, ada pengalaman menarik yang dikisahkan oleh Sweeney (1980). Pada tahun 1971 ada persetujuan antara TV Malaysia dan sekelompok pementas wayang kulit Melayu untuk mengadakan pertunjukan wayang secara berseri, episode demi episode, yang rekamannya akan ditayangkan oleh stasiun TV. Menjelang rekaman pertunjukan, terjadi kekacauan. Dalangnya tidak memiliki naskah tertulis, dan para pementas (dalang dan pemain 7 Sebagai contoh, secara pribadi saya sulit mempercayai kekuatan mantra yang terdapat dalam tembang Dhandhanggula Ana kidung rumeksa ing wengi ... (Ini adalah tembang yang berjaga menyelamatkan malam ...) Namun, bila saya melagukan tembang tersebut, saya tidak peduli lagi tentang isinya. Saya hanya menikmatinya sebagai tembang. Artinya, bagi orang Jawa moderen pun, poetic reading, sebagaimana yang dinyatakan oleh Arps, tetap berlaku. 8 Perlunya penguasaan pengetahuan lokal ini bukan hanya berlaku bagi etnopuitika. Almarhum Profesor Poerbatjaraka (1952), yang kedalaman ilmunya mengenai sastra Jawa kuno, tengahan, dan klasik tidak diragukan lagi, mengeritik kekurang-sempurnaan terjemahan dan analisis Kern dan Juynboll terhadap teks Ramayana dalam sastra Jawa kuno. Kemudian Poerbatjaraka menyatakan, Atur kula punika ngiras nenangi penggalihipun sedherek Jawai, ngaturi priksa bilih ing bab serat-serat Jawi taksih kathah sanget ingkang kedah dipun garap; dening sinten? Inggih dening tiyang Jawi piyambak. Awit yen boten tiyang Jawi piyambak inggih kados pundi-pundia, cekakipun mesthi boten saged dumugi ing raos (ejaan disesuaikan dengan Ejaaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan dan cetak tebal ditambahkan, hlm. 4-5). Arti dari kutipan tersebut, Apa yang saya sampaikan ini sekaligus bermaksud menggugah hati orang Jawa, memberitahu mereka bahwa teks-teks sastra Jawa (kuno) masih banyak sekali yang belum diteliti; oleh siapa? Ya oleh orang Jawa sendiri. Karena kalau bukan oleh orang Jawa sendiri, betapa pun (hebatnya si peneliti), dia tidak akan pernah sampai pada rasa bahasa . musiknya) tidak mau mengadakan gladi resik. Bahkan, ketika ditanya mau mementaskan cerita apa, dalangnya sendiri belum yakin apa yang akan dipentaskan. Maka, Sweeney, yang ditunjuk sebagai supervisor, diminta datang untuk mengatasi kekacauan tersebut. Dia pun datang ke studio rekaman, dan meyakinkan para pejabat dan pegawai di stasiun TV Malaysia bahwa segalanya akan beres dan berjalan dengan lancar. Kata Sweeney, I told the dalang the tale in three minutes and the recording began. For the next three hours, he translated that three-minute summary into a virtuoso performance. This was made possible by the fact that dalangs do not learn tales by heart; they create or re-create them in performance (Sweeney 1980: 41). Kalimat terakhir dalam kutipan di atas perlu digarisbawahi, bahwa para dalang tidak menghafalkan cerita; mereka mencipta atau mencipta-ulang cerita tersebut lewat pementasan. Hal ini juga berlaku bagi seni pedalangan Jawa; dalang yang menghafal cerita untuk dipentaskan akan diejek sebagai dalang buku . Artinya, ia belum mencapai ngelmu dalang yang sejati, yang selalu kreatif dalam setiap pertunjukan. Menurut asumsi saya, tuntutan terhadap kreativitas di dunia pentas ini juga berlaku dalam seni pedalangan Sunda, Bali, dan daerah-daerah lain di nusantara yang memiliki tradisi pewayangan. Sepengetahuan saya, wayang atau pertunjukan sejenisnya juga terdapat di negara-negara lain di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga di Cina. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kreativitas panggung merupakan persyaratan yang harus dikuasai oleh seorang dalang (atau apa pun istilah lokalnya). Berkaitan dengan pementasan TV wayang Melayu di atas, Sweeney selanjutnya menjelaskan bahwa, dalam pertunjukan wayang kulit itu, perkembangan alur cerita dan pemilihan tokoh serta bagian-bagian dramatik dari pentas tersebut dikendalikan oleh skemata psikologis sang dalang. Skemata wayang kulit Melayu itu merupakan pengetahuan pedalangan yang luas, yang terdiri dari perpaduan antara epik Ramayana dan cerita Panji. Keduanya memiliki kemiripan dalam alur cerita pokok, yang lazimnya dimulai dengan penculikan seorang puteri, pencarian puteri tersebut, peperangan antara para pencari dan penculik, dan kemudian happy ending, yang memadukan cinta-kasih antara sang puteri dan sang pencari. Skemata psikologis ini mengingatkan kita pada teori Perry-Lord yang terkenal itu, yang menyatakan bahwa penyair-lisan menguasai patokanpatokan khusus , berupa ungkapan-ungkapan puitis yang baku , yang membantu pementasannya mengalir dari satu kuplet ke kuplet lainnya, atau dari satu bait ke bait berikutnya. Analoginya, para dalang dan juru cerita tentunya juga memiliki patokanpatokan khusus yang tertancap sepanjang alur cerita , yang mengarahkan mereka menggerakkan lakon yang sedang mereka pentaskan. Jelaslah di sini bahwa pentas menjadi bagian utama dari obyek studi etnopuitika. Pentas ini pula yang secara tegas membedakan antara puitika (ala Jakobson) dan etnografi wicara atau the ethnography of speaking, yang dipopulerkan oleh Hymes sejak awal tahun 1960-an. Puitika Jakobson lebih memusatkan perhatian pada struktur teks; dan etnografi wicara Hymes mempelajari percakapan bahasa sehari-hari sebagaimana digunakan oleh penuturnya, serta bagaimana penggunaan bahasa itu ditentukan oleh konteks percakapan dan aturan-aturan yang berlaku dalam budaya lokal. Buku Hymes (1974), yang kini menjadi salah satu rujukan penting dalam sosiolinguistik, Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, merupakan hasil pemikiran yang lebih masak dari gagasan cikal-bakal yang ia kemukakan dalam The Ethnography of Speaking , sebuah artikel terkenal yang ia tulis pada tahun 1962. Menurut tinjauan linguistik, percakapan sehari-hari dipandang sebagai an unmarked (usual) way of speaking, sedangkan pentas sastra atau verbal art performance dipandang sebagai a marked (unusual) way of speaking. Jadi, etnopuitika atau puitikapentas, dengan terlebih dulu memahami nilai-nilai budaya lokal dan memusatkan perhatiannya pada pentas sastra, bertujuan menjelaskan unsur-unsur pembentuk struktur dan bunyi bahasa, yang merupakan ciri-ciri pokok dari pentas tersebut. Perlu dicatat, bahwa tujuan semacam ini sangat diwarnai oleh ilmu bahasa, yang sifatnya sangat struktural.9 Artinya, seperti telah dikemukakan di depan, analisisnya selalu bergerak dari bentuk menuju makna dengan kekuatan dan keterbatasannya (yang juga telah diutarakan). Penjelasan yang bersifat struktural, baik mengenai bentuk maupun bunyi bahasa, banyak diwarnai oleh metode puitika Jakobson; sedangkan penjelasan mengenai bagaimana budaya lokal itu mewarnai bahasa dan pentas sastra banyak berkaitan dengan hipotesis Sapir-Whorf, dalam versinya yang moderat. Berkaitan dengan hal ini, Sapir (1921: 225) menyatakan bahwa setiap bahasa, sebagai alat ekspresi budaya dan sastra, memiliki kekhasan masing-masing. Every language is itself a collective art of expression. There is concealed in it a particular set of aesthetic factors phonetic, rhythmic, symbolic, morphological which does not completely share with any other language. Sebagai contoh, dalam bahasa Sunda terdapat pantun dan dalam bahasa Jawa terdapat parikan yang struktur keduanya serupa, yakni terdiri dari sampiran dan isi; karena, kemungkinan besar, ada saling-pengaruh antar-budaya yang kemudian juga berakibat pada terjadinya saling-pengaruh antar-bahasa (termasuk di dalamnya penciptaan genre sastra). Bagi penutur bahasa Inggris, misalnya, the symbolic factor (meminjam istilah Sapir di atas) seperti pada pantun dan parikan itu merupakan hal yang asing sama sekali.10 Sebagai contoh lain, dalam sastra Jawa klasik, terutama dalam tembang macapat, aliterasi atau purwakanthi guru sastra (perulangan bunyi konsonan yang sama atau serupa) merupakan salah satu penanda penting bagi keindahan teks tembang. Menurut pengetahuan saya yang terbatas, purwakanthi yang sangat bagus, sehingga membuat tembang-tembang itu mengalir dengan enak ketika dilagukan, terdapat terutama dalam karya-karya Mangkunagara IV, misalnya dalam Wedhatama, Ngelmu, dan Tripama. Dalam sejumlah puisi bahasa Inggris terdapat juga aliterasi yang sangat menonjol, seperti dalam karya Gerard Manley Hopkins (misalnya The Windhover ) dan karya Edgar Allan Poe (misalnya The Raven ). Namun, ada perbedaan penting yang harus dicatat. Dalam tembang Jawa klasik aliterasi merupakan kelaziman, sedangkan dalam puisi-puisi bahasa Inggris aliterasi lebih merupakan perkecualian. 3. ETNOPUITIKA ALA HYMES DAN TEDLOCK: DUA MODEL DIHADAPKAN PADA SENI PEDALANGAN JAWA Bagaimana para peneliti di bidang etnopuitika memberikan penafsiran struktural terhadap pentas sastra? Di sini terdapat dua aliran-penafsiran besar yang berpengaruh: penafsiran ala Hymes, yang mengutamakan the universality of the lines, dan penafsiran ala 9 Bila latar belakang peneliti adalah antropologi atau folklore, misalnya, maka arah penelitian atau penekanannya akan berbeda. Para antropolog tentu lebih ingin tahu mengenai bagaimana suatu kelompok budaya merefleksikan diri lewat pentas sastra; sedangkan para ahli folklore lebih ingin mempelajari bagaimana berbagai alur cerita saling mempengaruhi, atau bagaimana sebuah alur cerita berubah dari waktu ke waktu, atau dari satu tempat ke tempat lainnya. 9 Apakah hal ini berkaitan dengan tesis Kaplan (1966), yang menyatakan bahwa cara berpikir Barat cenderung lurus dan linier, sedangkan cara berpikir Timur lebih bersifat tak-langsung atau sirkuler ? Tentunya diperlukan data-data yang lebih lengkap dan analisis yang akurat untuk mengiyakan atau menidakkan tesis Kaplan tersebut. Tedlock, yang menekankan pentingnya the art or aesthetics of sounding poetic texts. Menurut Hymes (1981, 1992, 1996), teks pentas sastra, yang bila ditranskripsikan secara ceroboh akan muncul menjadi teks prosa , pada hakekatnya adalah teks puisi . Misalnya, ketika ia melakukan transkripsi terhadap rekaman cerita-pentas dalam bahasabahasa Indian-Amerika, ia menyimpulkan bahwa cerita-pentas itu sebenarnya adalah puisi atau poetic narratives. Hal ini nampak dengan jelas pada hasil transkripsi cerita-pentas (serta terjemahannya dalam bahasa Inggris), misalnya, Chant to the Fire Fly dalam bahasa Chippewa, Cradle Song dalam bahasa Haida, dan Song of Chief s Daughter dalam bahasa Kwakiutl. Bahkan, dari penelitian-ulangnya terhadap teks-teks cerita-pentas yang berasal dari dasawarsa ketiga abad ke-20, Hymes menyimpulkan bahwa Sapir telah melakukan kesalahan pendengaran , dan akibatnya juga kesalahan transkripsi dan penerjemahan cerita-pentas dalam bahasa Wishram. Hymes (1981: 142) menyatakan, Sapir published the text and a translation in the volume Wishram texts (Sapir 1909a: 139-45). In that volume the original text occupies 93 lines. It is presented in 9 paragraphs as prose. The principle purpose of this paper is to show that the text represents some 168 traditional narrative lines, organized in some 56 verses. Di sini Hymes melakukan analisis rekonstruktif terhadap teks-teks tua yang dulu diteliti oleh Sapir, yang hasilnya kini adalah pembaitan prosa menjadi puisi. Terhadap penemuan puisi yang tersebunyi dalam prosa naratif itu, Hymes merasa terkejut dan sekaligus senang dan bangga. The discovery of such patterning was a surprise (and a delight). I had worked with the Chinookan materials for almost twenty years without appreciating its presence (Hymes 1981: 319). Pertanyaanya kemudian, haruskah penafsiran tekstual terhadap cerita-pentas ala Hymes itu diikuti oleh para peneliti di bidang etnopuitika secara mutlak? Sebagai contoh kasus, marilah kita ambil teks tertulis yang terdapat dalam seni pedalangan Jawa. Di toko-toko buku di Jogja atau Solo, banyak dijual serat pedhalangan atau buku teks petunjuk pementasan sebuah lakon, yang antara lain berisi janturan (narasi puitisdeskriptif), kandha (narasi puitis-dramatik), antawacana (percakapan, baik yang menggunakan bahasa puitis maupun non-puitis), dan suluk atau chant yang lazimnya melantunkan petikan kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Keempat genre tersebut, kecuali suluk, tidak ditranskripsikan sebagai teks puisi menurut model Hymes. Jadi, salahkah para penulis serat pedhalangan tersebut? Tidak mampukah mereka membedakan antara teks prosa dan puisi? Di sini, yang salah adalah pertanyaannya. Keindahan puitis dalam bahasa janturan dan kandha, misalnya, bukan ditentukan oleh pelarikan atau pembaitan teksnya, tetapi terutama oleh pilihan kosakatanya. Dalam kedua genre tersebut, banyak sekali terdapat kosakata kawi, yaitu kosakata yang, dalam sastra (lisan) Jawa, terutama digunakan dalam tembang dan seni-pentas (seperti wayang kulit, wayang orang, dan kethoprak). Artinya, keindahan puitis dari pentas sastra di dunia Jawa terutama ditentukan oleh pilihan ragam bahasanya (yang oleh Poedjosoedarmo at al. (1986) disebut ragam panggung ), dan bukan oleh pelarikan dan pembaitan teksnya. Maka, the universality of the lines dalam model Hymes, yang berupaya menemukan puisi dalam setiap pentas sastra melalui analisis tesktual, ternyata tidak lagi universal kebenarannya ketika dihadapkan pada dunia lokal Jawa . Kesimpulannya, metode etnopuitika yang dikemukakan oleh Hymes memang menunjukkan kelebihan dan keunggulannya, tetapi sekaligus juga kelemahan dan keterbatasannya. Sebagaimana Hymes, Tedlock juga tertarik pada pelarikan dan pembaitan dalam mentranskripsi dan menerjemahkan cerita-pentas dari berbagai kelompok budaya yang masih memiliki tradisi lisan yang kental, seperti masyarakat Zuni di Amerika Serikat dan masyarakat Maya di Meksiko. Namun, bagi Tedlock seni pengucapan teks (the art of sounding the narrative texts) lebih penting daripada pembaitannya. Oleh karena itu, ketika ia menerjemahkan teks cerita-pentas dari masyarakat Zuni dan Maya ke dalam bahasa Inggris, ia berusaha untuk memperdengarkan cerita-pentas tersebut kepada pembacanya. Untuk maksud ini, Tedlock menciptakan konvensi-konvensi ortografis baru dan menambahkannya ke dalam sistem tulisan yang ada (dalam bahasa Inggris). Misalnya, huruf besar untuk suara keras, garis panjang di belakang vokal untuk bunyi vokal yang sangat panjang, tanda-titik pemisah larik untuk berhenti dua detik , akhir larik untuk berhenti setengah detik , dan beberapa tanda-baca baru lainnya. Bila kita kaitkan dengan fonologi dan fonetik, dapat diibaratkan bahwa tulisan yang telah ada merupakan broad transcription, sedangkan penulisan teks pentas model Tedlock adalah narrow transcription. Semua konvensi baru dalam ortografi Tedlock dapat dianggap sebagai diacritics dalam narrow transcription. Penulisan teks model Tedlock ini bertujuan membimbing pembaca, yang ingin mendengarkan keindahan cerita tersebut secara sempurna, untuk membacanya dengan keras lewat bimbingan tanda-baca baru tersebut. Berikut adalah sebuah contoh, diambil dari cerita The Girl and the Protector , yang diterjemahkan oleh Tedlock (1983: 103) dari bahasa Zuni. Then he told them his name: I AM THE PROTECTOR , he told them. His wife asked him, WHAT IS THE PROTECTOR? she said. Well, I am the Protector and my other name is MA ASEWI , he said. And her father spoke: Daughter, because of him there is a_____ll the EARTH. YOU MUSTN T ASK ANY QUESTIONS. It is good ... Susah-payah Tedlock untuk memperdengarkan cerita-pentas itu kepada pembacanya patut dihargai. Apa yang dilakukan Tedlock juga mengingatkan kita bahwa bahasa tulis pada hakekatnya hanya mewadahi sebagian saja dari totalitas bahasa lisan. Sebagaimana metode Hymes dinafikan oleh sejumlah data dalam serat pedhalangan, teknik penulisan Tedlock ini pun menghadapi tantangan yang sama, atau bahkan lebih besar dan lebih berat. Dalam wayang Jawa dan tentunya juga wayang Sunda, Bali, dan Melayu setiap tokoh memiliki warna suara dan nada serta cara bicara yang khas. Orang Jawa yang menyukai wayang dan mendengarkan rekaman audio dari pentas-wayang oleh almarhum Ki Nartosabdho,11 misalnya, akan langsung tahu dalam beberapa menit tokoh mana sedang berbicara dengan tokoh mana meskipun pada bagian percakapan itu tak ada sapaan atau nama yang disebutkan. Suara-suara yang sangat khas dan mudah dikenali adalah suara para tokoh wayang seperti Werkudara, Kresna, Baladewa, Narada, Cakil, dan keempat punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ada pula suara-suara yang mirip namun tetap berbeda, misalnya, suara Arjuna dan Abimanyu, suara Kresna dan Karna, atau suara Dursasana dan Pragota. Hebatnya, seorang dalang sekualitas Nartosabdho faham betul akan watak setiap tokoh wayang, dan ketika tokoh itu berbicara , bukan hanya suaranya yang khas, tetapi juga aspek kepribadian masingmasing ikut muncul dengan jelas. Suara groyok dan watak brangasan namun lurus dan jujur pada Baladewa; suara besar bernada rendah disertai gereng-gereng dan selalu menggunakan tingkat tutur ngoko pada Werkudara; suara tinggi melengking dengan cara 11 Sebagai contoh kekhasan suara setiap tokoh wayang, saya langsung memilih rekaman pentas oleh almarhum Ki Nartosabdho, karena sampai saat ini, dalam hal menampilkan kekhasan suara setiap tokoh wayang, belum ada dalang lain yang mampu menandingi kehebatan beliau dalam ber-antawacana. bicara amat cepat disertai watak sombong namun bodoh pada Cakil ketiganya merupakan contoh mengenai betapa beragam dan kayanya sastra lisan dalam pedalangan Jawa. Berhadapan dengan rekaman antawacana (percakapan) seperti di atas, apakah yang dapat dilakukan oleh Tedlock? Seandainya sistem transkripsi ala Tedlock itu dilipatkan sepuluh atau bahkan duapuluh kali kerumitannya, sistem itu tetap tak mampu mewadahi kekayaan sastra-pentas dalam pedalangan Jawa. Bila kita kembali kepada serat pedhalangan dan orang Jawa yang suka wayang, pertanyaan yang relevan adalah: Apa yang terjadi dalam pikiran atau batin orang Jawa ketika ia membaca serat pedhalangan? Sewaktu membaca teks percakapan atau antawacana, misalnya, ia langsung dapat mendengarkan suara masing-masing tokoh di atas, dan tentu saja juga suara tokoh-tokoh penting lainnya.12 Secara budaya, proses batin itu menjadi ingatan kolektif manusia Jawa, yang mengerti dan menikmati indahnya pentas-wayang. Artinya, pentas-wayang itu dimungkinkan oleh adanya ingatan kolektif tersebut. Ingatan kolektif ini sejenis langue dalam linguistik modern yang dipelopori oleh de Saussure, sedangkan antawacana yang memukau tersebut adalah sebagian dari parole-nya. Dari contoh percakapan wayang Jawa ini dapat ditarik kesimpulan: the art of sounding narrative or literary texts, dalam penelitian etnopuitika, tidak sesederhana asumsi atau tesis Tedlock. Warna lokal ternyata merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Jika dilihat secara global, justru warna lokal inilah yang menunjukkan bahwa tambang emas pentas sastra ternyata ada di mana-mana di seantero jagad. Ia menunggu para peneliti untuk menggali dan memprosesnya menjadi kekayaan sastra dan budaya internasional. Bila dikaitkan dengan antropologi, warna lokal itu dikukuhkan oleh Geertz (1983) dalam Local Knowledge, yang antara lain menyatakan bahwa yang lokal selalu terkandung dalam dan terkait dengan yang universal. Even in its most universalist moods [...] it [i.e., cultural anthropology] has always had a keen sense of the dependence of what is seen upon where it is seen from and what it is seen with. To an ethnographer, sorting through the machinery of distant ideas, the shapes of knowledge are always ineluctably local, indivisible from their instruments and their encasements (cetak miring ditambahkan, hlm. 4). Apakah arti kutipan dari Geertz ini bagi etnopuitika? Pengetahuan lokal , yang dipersyaratkan oleh etnopuitika, ternyata sejajar dengan tesis penting dalam antropologi budaya. Implikasinya adalah: kerjasama etnopuitika dengan antropologi dan cabangcabang lain dari ilmu budaya menjadi lebih mudah selama yang lokal maupun yang universal tidak ditonjolkan secara berlebihan atau bahkan dimitoskan. Bila kita kembali pada etnopuitika model Hymes dan model Tedlock di atas, keduanya memiliki semangat atau motivasi yang sama, yaitu berupaya menemukan nilai-tersembunyi dalam dunia lokal, untuk kemudian diangkat ke pentas universal. Ketika dihadapkan pada seni pedalangan Jawa, ancangan etnopuitika ala Hymes dan Tedlock ternyata kandas dan mentog. Maka, yang dapat kita ambil sebagai pelajaran adalah semangat atau motivasinya. Dengan semangat atau motivasi memperkaya yang universal melalui pemahaman dan penghargaan terhadap yang lokal, maka etnopuitika akan dapat 12 Untuk menikmati pentas wayang, orang Jawa lebih suka mendengarkan rekaman audio daripada membaca cerita wayang, termasuk serat pedhalangan. Alasannya jelas, yaitu di samping kekhasan suara setiap tokoh, di sana banyak hal lain yang tak tertampung oleh bahasa tulis. Ada alunan suara gamelan, ada dhodhok cempala dan gemerincing serta ledakan kepyek, ada nyanyian para waranggana yang mengiringi dan juga mengerem laju pentas-pertinjukan, dan lain-lain. Artinya, keindahan pentas-wayang yang bersifat auditory tak dapat dipindahkan ke dalam teks tulis yang bersifat visual. secara terus-menerus mendewasakan diri, memperkuat landasan teoritisnya, dan mengembangkan cakrawala pemikiran di bidang sastra pentas. 4. EPILOG: DI INDONESIA, ETNOPUITIKA MAU KE MANA? Dalam setiap bidang ilmu, orang sering berbicara mengenai keunggulan atau kehebatan suatu teori. Bidang studi linguistik, misalnya, pernah digegerkan oleh hebatnya teori atau revolusi Chosmky. Namun, setelah para bahasawan lain menyimak selama beberapa dasawarsa dan melihat teori Chomsky hanya berakrobat di bidang sintaksis, muncullah berbagai sub-bidang studi baru dalam linguistik, yang mempelajari penggunaan bahasa menurut konteksnya, atau sebagaimana ditentukan oleh nilai-nilai sosiokultural yang berlaku bagi penuturnya. Dengan.kata lain, berbagai sub-bidang studi seperti pragmatik, analisis wacana, analisis percakapan, sosiolinguistik, dan linguistik antropologi untuk menyebut beberapa contoh merupakan reaksi terhadap keterbatasan teori Chomsky. Atau, semua itu merupakan pemberontakan terhadap semangat revolusi Chomsky. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah sebuah contoh kasus, yang tidak hanya berlaku di bidang linguistik. Dalam bidang studi lain yang berkaitan dengan tradisi lisan, seperti dalam sastra (lisan), antropologi, folklore, dan berbagai disiplin lain dalam ilmu budaya, tentunya juga terjadi hal yang mirip atau sama. Artinya, setiap saat muncul teori baru yang menyatakan diri lebih hebat atau lebih canggih daripada teori-teori yang telah ada sebelumnya. Yang menarik, setiap bidang ilmu lazimnya menapak maju dengan cara tersebut, yaitu melalui pemberontakan baik dalam skala kecil maupun besar, baik secara halus maupun kasar terhadap teori yang telah ada. Sebagaimana dijelaskan di depan, munculnya etnopuitika pun disebabkan oleh ketidak-puasan terhadap teori puitika Jakobson dan kekurang-sempurnaan etnografi wicara ala Hymes. Sebagian besar ahli etnopuitika setuju untuk memasukkan etnopuitika menjadi bagian dari etnografi wicara. Memang layak juga dinyatakan bahwa ethnopoetics pada dasarnya merupakan kependekan dari ethnographic poetics. Dan di sinilah etnopuitika bertemu dengan dan menjadi bagian dari etnografi wicara. Artinya, pengetahuan lokal yang merupakan prasyarat bagi penelitian etnopuitika harus dilakukan melalui studi etnografis. Peneliti harus turun ke lapangan untuk dapat sepenuhnya memahami kerangka serta pernik-pernik dari pengetahuan lokal tersebut. Dalam pengalaman penelitian saya, yang laporannya saya tulis menjadi disertasi Wedding Narratives as Verbal Art Performance: Explorations in Javanese Poetics (Kadarisman 1999), penelitian lapangan itu memang sangat banyak membuahkan hasil. Di sana sering kali muncul hal-hal baru yang tak terduga sebelumnya. Ternyata benar bahwa peneliti harus senantiasa bersiap-siap to expect the unexpected. Ini bukan berarti bahwa the unexpected tersebut akan membelokkan arah penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Tidak demikian. Ia lazimnya hanya memperkaya hasil penelitian kita, dan sekaligus memberikan insights baru terhadap bidang ilmu yang kita geluti. Sebagai contoh, sementara melakukan rekaman narasi pengantin Jawa model priyayi (akhirnya terkumpul sebanyak 24 kaset audio dan 1 kaset video), saya berhasil pula merekam satu narasi pengantin Jawa model wong cilik. Transkripsi dari rekaman yang terakhir ini sangat berbeda dengan semua transkripsi narasi pengantin model priyayi, baik struktur bahasa maupun isinya, serta jenis-jenis simbolisme yang digunakan di dalamnya. Pada bagian Directions for Future Research dalam disertasi tersebut, saya menyarankan agar dilakukan penelitian narasi pengantin Jawa model wong cilik sebagai pembanding, dan sekaligus pelengkap, bagi penelitian yang telah saya lakukan. Sayang, sampai saat ini saran tersebut belum bisa dilaksanakan atau, lebih tepatnya, belum bisa saya laksanakan. Topik lain yang saya sarankan untuk diteliti lebih lanjut, antara lain, tembang dolanan yang dalam bahasa Inggris disebut children lores atau children verses. Di negeri Inggris maupun Amerika Serikat hal itu telah dilakukan secara cermat, dan kemudian dibukukan oleh para ahli folklores di kedua negara tersebut (periksa Opie & Opie 1959, dan Knapp & Knapp 1976). Sampai dengan akhir dasawarsa 1960-an atau awal 1970-an, singiran atau nadhoman di dunia pesantren dan madrasah masih nyaring terdengar. Yang menarik, hal ini tercermin lewat salah satu judul makalah Jakobson, Grammar of Poetry and Poetry of Grammar , meskipun, tentu saja, Jakobson tidak pernah mengenal singiran atau nadhoman. Yang terdapat di dunia pesantren adalah grammar in poetry dalam arti yang sebenarnya. Bagi santri yang mempelajari bahasa Arab pada tingkat lanjut, kitab Alfiyyah (atau Seribu Kuplet yang mencakup gramatika bahasa Arab, terutama sintaksisnya), merupakan kitab wajib. Demikian pula fonetika al-Qur an, atau yang dikenal sebagai atTajwied, juga disyairkan dalam buku kecil berjudul Hid yatu-sh-Shibyaan, atau Petunjuk (Membaca al-Qur n) bagi Anak-anak . Ada lagi buku syi ir serupa bernama AqiedatulAwaam, yang berarti Teologi buat Orang Awam . Apakah yang telah terjadi? Gramatika dalam sajak di dunia pesantren dan madrasah, yang dulu selalu dilagukan dengan merdu, kini telah membisu. Bila Arps (1992) dapat mempelajari teks tembang Jawa dengan pendekatan etnopuitika, dan membuahkan hasil penelitian unggulan, seharusnya etnopuitika dapat pula digunakan untuk meneliti dan mempelajari kembali teks-teks dari gramatika dalam sajak , yang sampai saat ini mestinya masih dapat dilacak jejaknya di dunia pesantren. Daftar di atas tentu saja dapat diperpanjang dengan mengemukakan topik-topik lain yang relevan untuk diteliti. Namun, yang lebih penting memang bukan teori apa yang kita gunakan, tetapi seberapa jauh dan seberapa dalam kita mampu menyelami obyek penelitian yang sedang kita kaji. Keberhasilan Arps tersebut bukan karena dia menggunakan ancangan etnopuitika, melainkan karena keluasan kajian pustakanya, kecermatan pengamatannya di lapangan, ketuntasan penguasaannya terhadap perangkat serta obyek penelitian, dan ketajaman serta kedalaman analisisnya terhadap data yang ia temukan di lapangan. Amin Sweeney, selama lebih dari tiga dasawarsa, terus-menerus melakukan penelitian di bidang Malay story telling tanpa pernah menggunakan istilah etnopuitika , tetapi karya-karyanya diakui oleh dunia akademis dan berpengaruh secara internasional. Seandainya diizinkan, maka saya akan langsung memberinya label hasil penelitian etnopuitika . Seperti teori atau pendekatan yang lain, etnopuitika memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Ini mengingatkan kita pada pernyataan terkenal dari Sapir (1921: 38), All grammars leak . Bila diproyeksikan, pernyataan ini menyarankan, tak ada teori atau ancangan teoritis yang tak bocor. Seperti telah dikemukakan di depan, teori linguistik Chomsky ternyata bocor; dan metode etnopuitika ala Hymes maupun Tedlock juga bocor. Dengan kata lain, ketika membicarakan suatu bidang ilmu pada tingkat abstraksi, kita tidak dapat melepaskan diri dari ancangan teoritis; namun kita juga harus menyadari bahwa setiap teori atau teori apa pun yang kita gunakan sebagai ancangan penelitian selalu memiliki keunggulan dan kekurangannya. Di forum Semiloka Nasional Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) ini, etnopuitika sebagai ancangan penelitian sekedar diperkenalkan, dan tidak dijual atau diiklankan. Bila para peneliti tradisi lisan di Indonesia dapat memungut hal-hal yang nampak menjanjikan dalam etnopuitika, maka ancangan teoritis ini masih perlu diujicoba berulang-kali di lapangan, untuk dilihat hasil dan manfaatnya. Pada akhirnya, meminjam kata-kata Kennedy, don t ask what the ATL can do for you, but ask what you can do for the ATL. Semoga makalah singkat tentang etnopuitika ini merupakan sumbangan berharga buat ATL, betapapun kecilnya. DAFTAR PUSTAKA Allen, Harold B. 1964. Readers in applied English linguistics (second edition). New York: Appleton-Century-Crofts. Arps, Bernard. 1992. Tembang in two traditions: Performance and interpretation of Javanese literature. Southampton: Hobbs the Printers Ltd. Bauman, Richard. 1977. Verbal art as performance. Rowley, Mass.: Newbury House. Bauman, Richard. 1986. Story, performance, and event: Contextual studies of oral narrative. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Bauman, Richard. 1992. Performance. In Bauman, Richard (ed.). Folklore, cultural performances, and popular entertainments, pp. 41-49. New York/Oxford: Oxford University Press. Bauman, Richard & Briggs, Charles L. 1990. Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, 19: 59-88. Bauman, Richard, and Joel Sherzer (eds.). 1974. Explorations in the ethnography of speaking. Cambridge/New York: Cambridge University Press. Crystal, David. 1991. A dictionary of linguistics and phonetics. Basil Blackwell. Culler, Jonathan. 1975. Structuralist poetics: Structuralism, linguistics, and the study of literature. Ithaca, New York: Cornell University Press. Culler, Jonathan. 1997. Literary theory: A very short introduction. Oxford/New York: Oxford University Press. Florida, Nancy K. 1987. Reading the unread in traditional Javanese literature. Indonesia, 44: 1-15. Geertz, Clifford. 1983. Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, Inc., Publishers. Haugen, Einar & Bloomfield, Morton. 1973. Language as a human problem. New Yor: W. W. Norton & Company, Inc. Hill, Archibald A. 1969. Linguistics today. New York/London: Basic Books Inc., Publishers. Hunter, J. Paul. 1991. The Norton introduction to poetry (fourth edition). New York/ London: W. W. Norton & Company. Hymes, Dell. 1962. The ethnography of speaking. In Gladwin, T. & Stutervan, W. (eds.). Anthropology and human behavior. Washington, D. C.: Anthropoligical Society of Washington. Hymes, Dell. 1974. Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Hymes, Dell. 1981. "In vain I tried to tell you": Essays in native American ethnopoetics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Hymes, Dell. 1992. Ethnopoetics. In Bright, W (ed.). International Encyclopedia of Linguistics. New York, Oxford: Oxford University Press. Hymes, Dell. 1996. Ethnography, linguistics, and narrative inequality. Bristol, PA: Taylor & Francis Inc. Jakobson, Roman. 1960 [1987]. Linguistics and poetics. In Pomorska, K. & Rudy, S. Roman Jakobson, Language in Literature, pp. 62-94. Cambridge, Mass., London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. Kadarisman, A. Effendi. 1999. Wedding Narratives as Verbal Art Performance: Explorations in Javanese Poetics. Disertasi Ph.D. (tidak dipublikasikan). University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA. Knapp, Herbert & Knapp, Mary. 1976. One potato, two potato ... : The folklore of American children. New York/London: W. W. Norton & Company. Lord, Albert B. 1960. The singer of tales. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Newmeyer, Frederick J. 1983. Grammatical theory in the United States: Its limits and possibilities. Chocago and London: The University of Chicago Press. Opie, Iona & Opie, Peter. 1959. The lore and language of school children. London: Oxford at the Clarendon Press. Poedjosoedarmo, S., G. Soepomo, Leginem, & A. Suharno. 1986. Ragam panggung dalam bahasa Jawa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Poerbatjaraka, R. M. Ng. 1952. Kapustakan Jawi. Jakarta, Amsterdam: Penerbit Jambatan. Robson, Stuart. 1990. The Wédhatama: An English translation. Leiden: KITLV Press. Russel, D. A. & Winterbottom, M. 1998. Classical Literary Criticism. Oxford, New York: Oxford University Press. Sapir, Edward. 1921. Language: An introduction to the study of speech. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. Saussure, Ferdinand de. 1959. Course in general linguistics (English translation by Baskin, W.). New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company. Sherzer, Joel. 1990. Verbal art in San Blas: Kuna culture through its discourse. Cambridge: Cambridge University Press. Sherzer, Joel, & Anthony C. Woodbury (eds.). 1987. Native American discourse: Poetics and rhetoric. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Strand, Mark. 1991. Introduction. In Strand, Mark and Lehman, David (eds.) The Best American Poetry 1991. New York: Collier Books, Macmillan Publishing Company. Sukatno, Anom. 1993. Janturan lan pocapan ringgit purwo. Surakarta: C.V. Cendrawasih. Sukatno, Anom. 1992. Serat pedhalangan: Lampahan Bimo Suci. Surakarta: Cendrawasih. Sweeney, Amin. 1974. Professional Malay stroy telling: Some questions of style and presentation. Ann Arbor: Center for South and South Asian Studies, University of Michigan. Sweeney, Amin. 1980. Authors and audience In traditional Malay literature. Berkeley: Center for South and South East Asian Studies, University of California. Sweeney, Amin. 1994. Malay world music: A celebration of oral creativity. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tedlock, Dennis. 1983. The spoken word and the work of interpretation. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Tedlock, Dennis. 1992. Ethnopoetics. In Bauman, Richard (ed.). Folklore, cultural performances, and popular entertainments, pp. 81-85. New York/Oxford: Oxford University Press. Todorov, Tsvetan. 1981. Introduction to poetics (English translation by Howard, R.). Minneapolis: University of Minnesota Press. Woodbury, Anthony C. 1987. Rhetorical structure in a Central Alaskan Yupik Eskimo traditional narrative. In Sherzer, Joel & Anthony C. Woodbury (eds.). 1987. Native American discoure: Poetics and rhetoric. Cambridge: New York: Cambridge University Press.