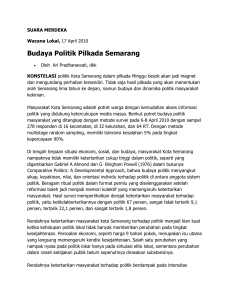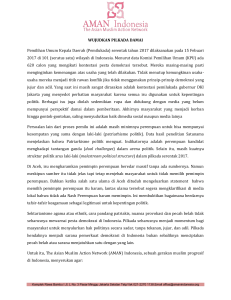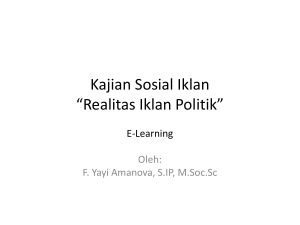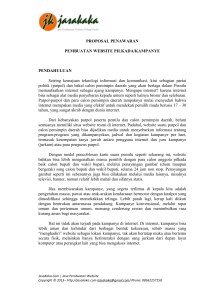CALON PRESIDEN INDEPENDEN DAN TANTANGAN PARTAI
advertisement

CALON PRESIDEN INDEPENDEN DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK Oleh: Muhamad Rosit Di era Reformasi, demokrasi elektoral kita sudah memberikan ruang kepada calon perseorangan dalam Pilkada, baik itu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun tidak untuk calon presiden Independen, Mahkamah Konstitusi masih berpegang teguh pada UU 1945 Pasal 6 A ayat (2) bahwa pasangan capres atau cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Padahal, dibukanya kran capres independen berpotensi memunculkan caprescapres yang memiliki potensial, kridibilitas, kapasitas dan leadership yang tak kalah saing dengan capres dari parpol. Hadirnya capres independen akan menjadi oase demokrasi di tengah kian menguatnya oligarki politik dan budaya politik transaksional yang kian merajalela. Merujuk pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, tidak disahkannya capres independen berarti masih tersumbatnya kran hak-hak politik warga untuk dipilih dalam pemilu. Dan itu berarti membelenggu regenerasi kepemimpinan nasional dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: Capren Independen, Tantangan Partai Politik dan Pelembagaan Pemilu Pendahuluan Berbicara tentang konsep kedaulatan rakyat adalah berbicara mengenai implementasi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Serta terjaminnya hak-hak politik rakyat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi merevisi beberapa pasal dalam UU No.32 Tahun 2004 antara lain Pasal 59 (3) yang diubah menjadi “membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”. Keputusan MK meloloskan calon independen, tentu saja memberikan harapan baru bagi munculnya calon-calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang relatif lebih terbuka bagi siapa pun yang memiliki minat untuk mencalonkan diri. Selama ini, peraturan yang memberikan 1 kewenangan partai politik dalam proses perekrutan politik tidak memberikan peluang yang demokratis dan transparan, bahkan disalahgunakan oleh sebagian elit parpol untuk mematikan proses perekrutan politik yang demokratis. Tidak mengherankan jika partai telah dianggap sebagian masyarakat sebagai lembaga perantara politik yang “memeras” kandidat yang ingin menjadi kepala daerah. Persepsi tersebut tidak mudah dibuktikan, tetapi gejala ini bukan lagi sekadar rumor melainkan telah menjadi isu politik yang mencemaskan dan menggerogoti masa depan demokrasi Indonesia. Calon independen merupakan calon perseorangan yang dapat mengikuti pilkada meskipun tanpa ada dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Posisi calon independen dalam pilkada merupakan suatu bentuk yang mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat yang ingin menjadi pemimpin, namun terbatas atau tidak adanya dukungan politik dari partai-partai politik (Cakra Arbas, 2012). Oleh karena itu, calon independen hadir sebagai salah satu solusi, supaya partai politik tidak bersikap semaunya dan lebih mereformasi rekrutmen politik yang selama ini tidak dijalankan secara konsisten. Calon independen tidak terikat oleh partai politik sebagaimana pencalonan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon independen memang tidak diusung oleh partai politik, melainkan pencalonannya memperoleh legitimasi secara langsung dari rakyat yang menjadi konstituennya. Jadi tidak ada istilah ‘balas budi’ kepada pihak-pihak yang merasa mengusung dan membesarkannya. Namun jika calon independen memenangkan pilkada, maka ia harus konsentrasi bagaimana memenuhi janji-janji politiknya dan bisa memainkan peran di tengah kuatnya aroma kepentingan perwakilan dari partai politik. Calon independen menjadi “alternatif” di tengah oligarki politik. Di samping itu, juga adanya bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap elit politik yang setelah meraih jabatannya kurang memperhatikan rakyatnya. Serta, kepentingan yang paling utama adalah masyarakat di tingkat lokal memiliki spektrum yang lebih luas dalam memilih pemimpin. Dengan semakin luas spektrum pilihan yang dimiliki, maka masyarakat di tingkat lokal lebih leluasa untuk memilih calon yang dianggap paling merepresentasikan mereka. Masyarakat merasa lebih puas jika kepentingan atau kelompok mereka ada yang mewakili di dalam pilkada. 2 Dampak Pilkada Langsung Di era Reformasi, proses demokrasi telah melahirkan perubahan-perubahan secara signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Proses pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR/DPRD dan DPD) yang dilaksanakan secara langsung pertama kali pada Pemilu 2004, menjadi titik awal terbukanya kran demokrasi yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Dari sini, kita melihat bahwa ada sebuah perubahan pola pemilihan yang akan berdampak terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Kemudian mengilhami proses demokrasi pada tingkatan Pilkada yang sebelumnya masih menggunakan pola pemilihan lama (melalui sistem perwakilan dari DPRD) menjadi pola pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan babak baru sekaligus momentum politik penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggarakan kepala daerah secara langsung diharapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas berdemokrasi di daerah itu sendiri. Tentu pemilihan kepala daerah secara langsung ini menjadi modal besar yang berharga, bagi proses proses pembangunan di segala bidang (Rozali, 2007). Berangkat dari proses pilkada secara langsung yang dimulai sejak 1 Juni 2005, kita bisa melihat bahwa harapan itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Dikatakan pilkada secara langsung, makna langsung di sini lebih terfokus kepada adanya hak pilih dari rakyat untuk memilih kepala daerah. Pilkada langsung merupakan upaya demokrasi untuk mencari pemimpin di daerah yang berkualitas, akuntabel, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Menurut J. Kristiadi, pilkada langsung yang selama berlangsung menampilkan wajah yang sama sekali berbeda.Wajah pertama yaitu menunjukkan sisi gelap pilkada di mana pilkada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan oleh segelintir elit partai politik untuk mendapatkan kekuasaan pada lembaga eksekutif daerah. Wajah kedua, menunjukkan adanya secercah harapan bagi perkembangan demokrasi ke depan karena telah terjadi proses transformasi politik melalui pergeseran pola pemilihan dari model elite vote ke model popular vote yang berarti menggeser arena politik yang semula dimainkan oleh DPRD (Amiruddin dan Zaini Bisri, 2006). Ada dua alasan mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Pertama, agar lebih konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial antara lain ditandai oleh pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Karena itu sebagaimana pada tingkat nasional presiden sebagai kepala pemerintahan 3 dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka untuk kepala daerah otonom juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan memilih secara langsung siapa yang memimpin suatu daerah, rakyat yang berhak memilih dapat menentukan kepala daerah macam apakah yang akan memimpin daerahnya, dan dapat menentukan pola dan arah kebijakan macam apakah yang akan dibuat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan daerah. Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek (checks and balances) antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah. Salah satu ciri pemerintahan yang menganut pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek adalah baik lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keduanya memiliki kekuasaan yang seimbang dengan tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya saling mengontrol melalui pembuatan peraturan daerah dan APBD, keduanya memiliki legitimasi dari rakyat. Dalam bahasa yang sering digunakan oleh elit lokal, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjamin agar kepala daerah menjadi mitra sejajar dengan DPRD. Dengan begitu interaksi DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah diharapkan tidak saja dinamis tetapi produktif bagi kesejahteraan masyarakat daerah (Surbakti, 2006). Ditinjau dari lingkungan kemasyarakatan (civil society), sesungguhnya pilkada langsung memiliki implikasi yang tidak kecil pula terhadap penguatan kehidupan politik masyarakat lokal kita. Paling tidak, pilkada memajukan lembaga kemasyarakatan dan menyehatkan perilaku politik masyarakat daerah kita di dalam lima hal sebagai berikut: Pertama, pilkada bakal meningkatan kesadaran politik masyarakat daerah dalam segenap proses pemilihan, mulai dari pendaftaran, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penetapan serta pelantikan calon terpilih. Pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap realitas politik di daerahnya akan kian meningkat seiring dengan keterlibatan, keaktifan, dan pengalaman mereka dalam berpemilu. Pendek kata, pemilihan kepala daerah menjadi suatu mekanisme perubahan politik yang teratur, tertib dan periodik, tidak menyeramkan, dan bahkan ditunggu-tunggu kedatangannya. Kedua, pilkada memicu aktivitas politik masyarakat di area lokal yang memberi kesempatan lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi dan mengembangkan organisasi madani. Pengorganisasian masyarakat lewat berbagai macam bentukl LSM dan ormas (civil society organization), pendidikan anggota masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, dan keterlibatan warga dalam segenap tahapan pemilihan merupakan latihan demokrasi bernilai 4 tinggi. Dengan begitu, proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah tidak hanya dilepaskan ke tangan segelintir elite di DPRD yang mengatasnamakan rakyat, tetapi dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder. Ketiga, pilkada memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, misalnya dengan turut langsung menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang akan membawa mereka menggapai mimpi hidup sejahtera dan bahagia serta tetap terus terlibat sebagai active citizen dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih sebagai janji janjinya pada waktu kampanye dulu, bahkan dalam mengawasi sang kepala daerah jika salah menggunakan kekuasaannya ketika memangku jabatan. Jadi pilkada memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirai rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan atau dia akan terjungkal dalam pilkada berikutnya. Keempat, pilkada memotivasi media lokal untuk lebih aktif terlibat dalam segenap tahapan pemilihan mulai dari pendaftaran pimilih hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Misalnya, tiras koran lokal akan naik , halamannya pun akan bertambah baik karena ada rubrik khusus pilkada maupun ada pemaasangan iklan oleh para calon. Informasi pemilihan dan sosialisasi pemilu juga akan ramai menghiasai media lokal kita. Tidak hanya itu media juga akan aktif mengkritisi dan juga mengawal segenap proses penyelenggaraan pilkada dari berbagai kelailaian dan penyimpangan yang merugikan masyarakat pemilih, baik yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemilihan maupun oleh pasangan calon serta partai politik. Dengan demikian, the power of media akan memberi kontribusi cukup besar bagi kelancaran jalannya pilkada. Kelima, pilkada mendorong berkembangnya spirit kemandirian di dalam tubuh partai politik di daerah dan sekaligus mengurangi intervensi pengurus pusat partai politik, karena pasangan calon yang ditampilkan agar dapat memenangi pemilihan mestilah yang punya nilai jual di mata pemilih di daerah itu, bukan karena pesanan bos partai dari Jakarta. Pilkada juga berpotensi untuk menumbuhkan demokrasi di kalangan internal partai politik di daerah lewat mekanisme konvensi, musyawarah atau muktamar partai yang menghargai kedaulatan anggota. Selain itu, lewat pilkada mesin partai politik di daerah akan berputar, sehingga menyehatkan tubuh partai. Jadi, kehadiran pilkada bisa menyuburkan kebhidupan partai politik di daerah (Thubany, 2005). 5 Lalu, apakah pilkada secara langsung ini mampu membangun relasi yang lebih baik antara kepala daerah dan DPRD dengan masyarakat? Salah satu argumen pokok yang mendasar dilaksanakannya pilkada secara langsung adalah mengembalikan otoritas kepada masyarakat. Melalui pilkada secara langsung, sistem representasi di dalam pemerintahan memang masih berlangsung, tetapi, sistem representasi yang dibangun melalui pilkada secara langsung lebih memberi ruang otoritas yang lebih besar kepada masyarakat dari pada sistem representasi yang mendelegasikan otoritas memilih kepala daerah kepada DPRD. Secara teoretis, relasi antara kepala daerah dengan masyarakat bisa berlangsung lebih baik pasca pilkada langsung ini. Dalam konteks akuntabilitas, kepala daerah harus menjalinnya secara langsung dengan masyarakat. Untuk itu, kepala daerah setiap tahun dituntut menyebarluaskan informasi tentang apa yang telah dikerjakan. Melalui informasi demikian, masyarakat tidak hanya bisa mengetahui tetapi juga bisa melakukan penilaian-penilaian apakah yang dikerjakan oleh kepala daerah itu sesuai dengan janji janji yang telah diberikan pada saat kampanye atau tidak. Sekiranya apa yang dikerjakan itu tidak mengecewakan, rakyat di daerah bisa memberikan hadiah, yaitu memilihnya kembali. Sebaliknya kalau mengecewakan, bisa memberikan hukuman, yaitu tidak akan memilih kembali. Di dalam situasi seperti ini, tingkat akuntabilitas kepala daerah yang dipilih secara langsung bisa berlangsung lebih baik daripada tingkat akuntabilitas kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan lebih lebih yang ditunjuk oleh pusat pusat kekuasaan pada masa pemerintahan Orde Baru (Marijan, 2010) Namun kenyataannya dalam pilkada secara langsung, dominasi partai politik masih begitu besar. Pilkada secara langsung akan memiliki makna yang lebih baik manakala terdapat desentralisasi sistem kepartaian. Sekarang ini mengingat sentralisasi partai politik masih kuat, rakyat di daerah masih belum bisa leluasa menentukan calon-calon yang diajukan di dalam pilkada. Realitas demikian tidak hanya memperkecil ruang penyeleksian pemimpin yang lebih terbuka, tetapi juga tidak mampu mewadahi realitas tentang munculnya fenomena anti partai politik. Oleh karena itu, calon independen merupakan salah satu alternatif untuk keluar dari dominasi partai politik yang sangat besar atau setidaknya menciptakan tantangan terhadap pencalonan dari partai politik. Dengan disahkannya calon independen, terjaminnya hak-hak politik warga negara untuk mencalonkan diri di pilkada secara independen, dan masyarakat di satu sisi juga memiliki kesempatan yang luas untuk menyeleksi calon-calon di pilkada. 6 Perangkingan Media dan Krisis Kepemimpinan Hadirnya calon Independen di pilkada dan wacana capres independen di Pilpres menjadi sinyal bahwa negeri ini krisis pemimpin yang berkualitas. Hal ini terjadi karena partai politik tidak menjalankan rekrutmen politik atau kaderisasi secara berjenjang. Pada akhirnya, ketika menjelang pemilu maupun pilkada, wajah-wajah lama masih menghiasi dan mendominasi kontestasi pemilu. Misalnya, hiruk-pikuk mengenai siapa yang pantas menjadi capres pada Pilpres 2014 kian menjadi wacana yang menguras perhatian publik. Karena dari semua presiden yang telah memimpin Indonesia, rupanya belum ada satupun yang bisa melakukan perubahan secara radikal. Mengamati sepak terjang calon presiden masih didominasi wajah-wajah lama yang berasal dari partai politik. Padahal, Indonesia membutuhkan sosok figur “baru dan segar” yang bisa menjawab segala bentuk permasalahan nasional. Selain itu, perangkingan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dan media massa sudah terjebak pada aspek popularitas dan elektabilitas belaka, padahal semua itu tak menjamin bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. Seharusnya lembaga survei dan lebih-lebih media massa bisa menstimulasi dan memunculkan sosok pemimpin yang segar, energik dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Bukan larut ke dalam “budaya popular” yang dangkal dan tiada memiliki dampak jauh ke depan. Dalam hal ini, media massa berperan besar dalam mengonstruksi citra calon presiden. Bahkan media massa dan lembaga survei bisa menggiring wajah-wajah capres. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mengimbangi upaya konstruksi media massa, misalnya para tokoh yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan Indonesia Memilih Pemimpin, yang dipelopori oleh Komarudin Hidayat dkk, dalam rangka mencari seorang pemimpin yang berkualitas yang memang tak dimediasi oleh media massa. Semua capres yang dirangking oleh media massa itu berasal dari tokoh elite partai, bahkan nyaris sebagian dari mereka sudah pernah bertarung pada Pilpres sebelumnya. Tak ada satupun capres dari perseorangan (calon independen) yang dirangking oleh media massa dan lembaga survei. Hal inilah yang harus kita kritisi, berarti persepsi media massa, faktor kepemimpinan itu menitikberatkan pada modal popularitas dan elektabilitas yang tinggi semata. Padahal dalam memilih pemimpin dibutuhkan syarat-syarat yang ketat, di antaranya. Pertama, 7 seorang pemimpin harus memiliki modal sosial. Modal sosial ini bisa berupa jaringan akar rumput masyarakat. Kedua, memiliki rekam jejak. Rekam jejak merupakan pengalaman atau prestasi saat menjadi pejabat publik. Ketiga, Modal intelektual. Seorang kandidat harus berpendidikan tinggi dan memiliki daya tangkap yang tajam serta berwawasan kebangsaan. Dan keempat, modal finansial. Ini merupakan modal dasar untuk menggerakkan segala mesin pemenangan calon. Lebih khusus lagi, bagi capres independen harus memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan calon dari parpol. Terutama personality atau personal branding sangat menentukan perilaku pemilih. Tantangan Cares dari Partai Politik Dinamika politik Indonesia kekinian menunjukkan bahwa partai politik hari ini dianggap tidak lagi memiliki taring. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol kian meningkat. Hal inilah yang barangkali menjelaskan mengapa Jokowi mampu keluar sebagai pemenang pada pilpres 2014. Koalisi besar partai politik ditumbangkan oleh personality dan track record Jokowi yang berhasil mencuri hati rakyat. Namun sangat disayangkan, kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla selama ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Bahkan Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat malah tersandera kepentingan partai koalisi. Kebijakan-kebijakannya kerapkali diintervensi oleh partai koalisi, sehingga presiden dan wakil presiden lebih mengakomodir kepentingan politik balas budi. Pada akhirnya, hal tersebut berimbas pada kinerja “kabinet kerja” yang belum memberikan kepuasan terhadap rakyat Indonesia. Menurut hasil survei bertajuk "Jelang Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya sebesar 57,5% dan 3,2% menyatakan sangat puas. Sedangkan mereka yang kurang puas tercatat 33,8% dan tidak puas sama sekali 3,7%, menurut hasil survei yang digelar pada 15 sampai 25 Maret 2015. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK terkait dengan persoalan ekonomi yang harus mendapat perhatian pemerintah, yakni sebesar 21,6%. Masalah penting lainnya menurut pendapat responden adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, yakni sebesar 19,6%. Sedangkan sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan dipandang sebagai masalah penting dengan porsi masing-masing 8,4% dan 6,7%. 8 Hal menarik dari hasil temuan itu adalah dimasukannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai permasalahan yang paling penting yang harus mendapat perhatian pemerintah dengan angka 14,6%. Artinya, masalah KKN tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK. Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintan juga diikuti oleh rendahnya ketidakpuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja. Masyarakat yang cukup puas kepada kinerja kabinet hanya sebesar 45,3% dan sangat puas 1,5%. Sedangkan mereka yang kurang puas sebesar 31,2% dan tidak puas sama sekali 2,2%. Dari hasil survei di atas, selain kinerjanya belum memuaskan rakyat, Jokowi – Jusuf Kalla belum bisa menjadi seorang presiden dan wakil presiden yang mandiri dan berwibawa. Karena setiap kebijakan publik yang menjadi otoritasnya kerapkali diintervensi oleh kepentingan partai koalisi. Oleh karena itu, calon presiden yang diusung partai politik banyak sekali menunjukkan kelemahan-kelemahannya yang berdampak terhadap kinerjanya. Misalnya, secara kelembagaan, salah satu kelemahan parpol adalah soal alur pendanaan. Dana internal partai politik (parpol) sangat tak memadai untuk membiayai pertarungan, sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak eksternal, antara lain donator dan para investor politik. Praktik ini, melahirkan perselingkuhan abadi penguasa-pengusaha (penguasaha) yang kerap mereduksi kesejatian demokrasi. Hal tersebut juga sering menjadi pembenar bagi praktik akumulasi ekonomi para politisi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Dalam konteks inilah, kita sering melihat peran parpol sebagai bunker bagi para koruptor. Sudah bukan rahasia jika BUMN, proyek-proyek kementrian, pemda-pemda, sirkulasi jabatan dan sejumlah kerja sama dengan pihak swasta, kerap kali menjadi pintu masuk tindakan korupsi para politis maupun para broker yang berafiliasi ke parpol tertentu (Heryanto, 2011). Merujuk pada realitas tersebut, pada akhirnya stigma yang terbangun adalah parpol sebagai lembaga yang koruptif dan tidak lagi mampu menjadi ladang persemaian calon pemimpin. Parpol bukan menjadi wahana penyampai ideologi atau saluran politik namun lebih sebagai mesin pengeruk anggaran. Stigma ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi partai politik dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Stigma kegagalan parpol yang lain adalah dalam merawat akar rumput. Konstituen tidak diposisikan sebagai bagian integral dari partai, namun hanya sebagai komoditas musiman. Mereka hanya dianggap berharga ketika masuk waktu-waktu pemilihan umum. Di luar itu, tidak 9 ada tali pengikat yang kuat untuk menyatukan mereka. Melalui pendekatan kesamaan ideologi misalnya. Terdapat tren di sejumlah negara yang memperlihatkan semakin meningkatnya proporsi non-partisan dalam pemilihan umum. Non-partisan adalah sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu. Kaum non-partisan melihat pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja yang dicanangkan partai atau kandidat. Fenomena non-partisan ini menunjukkan bahwa pemilih dewasa ini semakin kritis terhadap partai politik. Mereka tidak dengan mudah mengikatkan diri dengan suatu ideologi tertentu, karena perdebatan ideologi pasca perang dingin memang telah kehilangan energinya. Yang disimak pada masa ini tinggal seberapa besar kemampuan suatu partai untuk memecahkan permasalahan bangsa. Hal inilah yang menentukan bisa tidaknya suatu partai untuk mendapatkan suara dalam pemilu. (Firmanzah, 2008). Menjawab kekecewaan masyarakat terhadap partai politik, seyogyanya partai mulai berbenah dan bertranformasi menjadi partai modern. Menurut Gun Gun Heryanto, setidaknya ada empat ciri partai modern. Pertama, meminimalisir kekuatan rujukan (referent power). Tak disangkal bahwa setiap partai butuh figur atau tokoh simpul. Namun ketergantungan yang berlebihan terhadap figur dapat mengundang budaya feodal dan sistem dinasti politik. Misalnya saja di PDIP, tak ada yang salah jika menjadikan Soekarno sebagai figur sentral ideologi partai. Begitupun tak salah menempatkan Mega sebagai sosok sentral dalam beberapa periode kepemimpinan partai ini. Yang salah adalah munculnya asumsi jika tak dipimpin Mega, maka PDIP seolah akan kehilangan ruhnya. Terbukti, kongres PDI Perjuangan memilih Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum kembali tanpa ada satupun kompetitor internal PDI Perjuangan. Kedua, partai modern dibangun melalui kemampuan anggotanya untuk melakukan proses refleksivitas. Partai memfasilitasi anggota-anggota organisasinya mampu melihat ke masa depan dan membuat perubahan-perubahan di dalam struktur atau sistem jika diprediksi hal-hal tertentu tidak akan berjalan. Refleksifitas adalah kemampuan untuk menentukan alasan-alasan pilihan perilakunya. Dengan demikian, partai modern adalah partai yang progresif dalam beradaptasi dalam situasi dinamis. Ketiga, partai modern dibangun melalui tahapan kaderisasi. Ketiga tahapan tersebut, berjalan secara integratif yakni merekrut orang untuk bergabung dengan wadah partai, lantas 10 membina kader menjadi loyalis serta mendistribusikan kader ke dalam posisi-posisi tertentu. Perkembangan dinamis-pragmatis kerap menciderai tahapan kaderisasi ini. Partai kerap menjadi pintu masuk bagi munculnya politisi-politisi non-kader yang mengatasnamakan partai dalam perebutan jabatan publik tertentu. Keempat, partai modern harus mau dan mampu menjalankan fungsi-fungsi partai. Di antara fungsi-fungsi itu adalah menjadi saluran agregasi politik, pengendalian konflik dan kontrol. Bagaimanapun partai memiliki posisi penting dalam menstimulasi dan menunjukkan arah kepentingan politik yang semestinya menjadi perhatian publik. Capres Independen Pada Pilpres 2019 Disahkannya calon independen dalam Pilkada langsung merupakan terakomodirnya hakhak politik masyarakat untuk mimilih dan dipilih. Ini merupakan aplikasi demokrasi yang kian menunjukkan penghargaan kepada rakyat. Namun hak-hak politik itu sampai saat ini kemungkinan besar belum bisa diterapkan pada pemilihan Presiden 2019. Mahkamah Konstitusi belum mengesahkan capres independen untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan umum. Sehingga capres independen masih mengalami jalan terjal menuju Pilpres 2019. Kemunculan capres independen banyak sekali menemui hambatan, di samping isu ini masih menjadi konsumsi elit dan respons serta dukungan elit utama partai politik agak lemah. Aturan main dalam bentuk UU Pemilu ternyata tidak sesuai dengan harapan kalangan ini. Capres masih tetap akan sangat ditentukan oleh parpol seperti terdapat dalam UU Pemilu yang kemudian disahkan oleh DPR di mana parpol yang berhak mengajukan capres adalah parpol yang memperoleh 20 persen kursi dan 25 persen suara nasional. Itu berarti pintu masuk atau kesempatan capres independen untuk ikut berlaga menjadi tertutup atau bahkan hilang. Misalnya pada Pemilu 2009 lalu, dari beberapa nama capres independen pertama kali muncul nama Rizal Malarangeng yang secara terbuka menjagokan diri menjadi capres dengan mengiklankan di beberapa media massa. Dengan modal kapital yang dimiliki oleh Rizal dan popularitasnya serta posisinya sebagai pengamat politik nasional membuat bangunan popularitasnya tidak menuai hambatan. Namun karena respons masyarakat terhadapnya dingin dan kurang diminati, maka kemudian Rizal memutuskan mundur dari bursa pencapresan. Selain Rizal, tokoh muda lain yang gencar menjagokan diri menjadi presiden dan mendukung upaya-upaya agar capres independen mendapatkan legitimasi politik adalah Fadjroel 11 Rahman. Fadjroel dikenal sebagai intelektual politik dan tokoh LSM terkemuka. Berbeda dengan Rizal yang akhirnya memutuskan mundur karena respons dan dukungan politik kurang, Fadjroel tetap konsisten maju dan terus mewacanakan untuk judicial review aturan hukum syarat pencapresan dalam UU pemilu yang tidak mengakomodasi munculnya capres independen (Firmanzah, 2010). Kemudian, bagaimana dengan capres independen pada Pilpres 2019? Sampai saat ini pun Mahkamah Konstitusi sepertinya masih berpegang teguh pada UU 1945 Pasal 6 A ayat (2) bahwa pasangan capres atau cawapres yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal inilah yang menjadi sumbatan bagi capres independen tidak bisa ikut serta dalam ajang pemilihan umum. Sementara bursa calon presiden masih didominasi wajah-wajah lama yang notabene mereka adalah tokoh elite partai politik. Bagi kelompok yang menginginkan diakomodirnya capres independen mencoba melihat sisi lain dari konstitusi. Misalnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Dua sisi yang seolah paradoks inilah yang dianggap membutuhkan kejelasan sehingga memerlukan langkah amandemen. Kemudian, konteks politik yang terkait dengan fenomena disonansi kognitif yang dialami pemilih atas tawaran parpol yang berkutat di elite yang itu-itu saja. Disonansi kognitif biasanya muncul akibat perbedaan dari apa yang dipikirkan dengan realitas yang didapatkan dari para pemilih. Parpol di Indonesia hingga sekarang tidak memberi impresi yang kuat. Bahkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan publik atas peran dan fungsi partai. Apatisme publik terhadap eksistensi parpol ini semakin menjadi, di saat parpol-parpol ramai melibatkan diri ke dalam kekuasaan. Sejak reformasi hingga sekarang, DPR sebagai representasi kiprah partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan, ternyata gagal memberi keyakinan pada publik, bahkan semakin cenderung menguatnya gejala delegitimasi simbol wakil rakyat (Heryanto, 2011). Begitu juga dengan perilaku elite-elite parpol yang kian menujukkan sikap oligarkis. Budaya politik di partai politik masih biasa menempatkan ketua umum partai politik mempunyai otoritas untuk mencalonkan diri sebagai presiden dari partainya. Entah dia mempunyai 12 elektabilitas dan polularitas tinggi sebagai modal pencalonannya atau dia hanya bermodalkan kemauan agar bisa mencalonkan diri. Jadi, ketua umum partai politik adalah sebuah tiket khusus menuju pencalonan kursi presiden yang dengan sendirinya akan diakomodir dan diusung oleh partai politik yang dipimpin. Mekanisme konvensi partai dalam menyeleksi calon-colon pemimpin berkualitas sudah tak dijalankan, meskipun ada konvensi, konvensi itu tak sama dengan konvensi yang dijalankan di Amerika Serikat. Di AS konvensi dijalankan secara terbuka, transparan dan melibatkan masyarakat. Bukan konvensi yang lebih mementingkan gizi (uang) dari pada visi dan misi calon. Capres Independen di Amerika Jika di Indonesia capres independen belum bisa diakomodir, bagaimana dengan capres independen di Amerika? Apakah di negara tersebut capres independen lebih diminati dibanding calon dari parpol? Pada Pemilu Amerika tahun 2008, kandidat presiden Barrack Obama dan kandidat presiden Partai Republik John McCain, jauh lebih diminati dibanding calon-calon independen yang beredar sebelum fase pemilu nasional. Misalnya nama Ralp Neder yang berpasangan dengan Matt Gonzalez sebagai capres independen, ternyata tidak menarik minat warga AS. Di Pemilu AS tahun 2000 dan 2004 kita juga mengenal nama capres independen dari Ohio bernama Joe Schriner yang berpasangan dengan Dale Way dari Michigan. Para capres independen tersebut, tak laku jual karena warga Amerika cenderung lebih mempercayai kandidat yang berasal dari parpol. Satu mekanisme yang membuat kandidat parpol itu menarik minat pemilih adalah mekanisme konvensi. Bagaimana Obama harus bersusah payah mengalahkan Hillary Clinton guna merebut minimal 2.025 dari 2.049 delegasi pada pemilu nasional. Ini merupakan contoh bagi kita, jika partai menjalankan fungsinya dengan baik, maka sesungguhnya parpol tak perlu khawatir untuk bersaing dengan capres independen. (Heryanto, 2011) Berkaca pada pemilu di AS, sekali lagi, partai politik di Indonesia harus berbenah jika masih ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mereka harus menghapus citra parpol sebagai lembaga yang korup serta harus serius menggarap massa akar rumput. Citra oligarkis, feodal, dan traksaksional yang masih melekat pada tubuh parpol juga menjadi evaluasi wajib bagi parpol. 13 Calon Independen sebagai Katalisator Pada Pilgub Aceh 2006 merupakan calon independen yang pertama kali berkompetisi di Pilkada. Calon independen tersebut yakni pasangan Irwandi Yusuf-M. Nazar, mereka menang dengan 38,20 % suara. Pemilihan yang dilaksanakan pada 11 Desember 2006 tak ayal mengubah peta politik Aceh. Pasalnya calon independen di Aceh merupakan representasi dari GAM-SIRA yang ketika itu belum membentuk partai lokal. Pun begitu Pilgub Aceh 2006 tak pelak menjadi awal mula kemenangan calon independen di sebuah pemilihan umum daerah (Cakra Abas 2012). Kemudian, calon independen di Pilgup Aceh menjadi rujukan bagi implementasi calon-calon independen di daerah-daerah lain. Selain di Aceh, salah satu calon independen yang memenangi pilkada adalah pasangan Aceng Fikri dan Diky Candra. Mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut setelah memenangi Pilkada Garut 2008 dalam dua putaran, mengungguli kandidat dari PDIP-Partai Golkar dengan mengumpulkan 57 % suara. Banyak yang berpendapat bahwa kemenangan Aceng-Diky lantaran popularitas Diky Candra sebagai selebritis. Pada September 2011, Diky Candra menyampaikan pengunduran diri karena ketidakharmonisan hubungan dengan Aceng Fikri. Sebelum Pilkada, Diky dan Aceng berjanji untuk tidak membawa politik dalam jabatan pemerintahan mereka, dan Diky menilai Aceng Fikri telah mengkhianatinya dengan masuk ke Partai Golkar dan menjabat sebagai wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Adapun di Jakarta, calon independen yang ikut berkontestasi di Pilgub DKI 2012 tak seberuntung calon independen di Garut maupun Aceh. Di Jakarta pasangan Faisal Basri dan Biem Benyamin hanya memperoleh suara 4,98 % (215.935). Namun mereka unggul dari pasangan Alex-Nono (calon dari Partai Golkar) yang mendapat 4,67 % suara (202.643). Perihal sedikitnya suara yang diraup Faisal-Biem disinyalir karena masuknya Jokowi dalam pertarungan Pilgub DKI. Faisal dan Jokowi memiliki ‘pasar’ yang sama, yakni kalangan menengah ke atas dan pemilih rasional. Selain juga gaya komunikasi Faisal yang kerap kali terlihat agresif dan sangat antipartai. Gaya seperti itu tampaknya belum bisa diterima masyarakat kebanyakan. Pada Maret 2012, Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) melakukan polling yang yang hasilnya menarik untuk dicermati. Sebanyak 46 % dari 1180 responden menyatakan calon gubernur DKI yang paling ideal merupakan calon dari independen. Adapun 32 % 14 responden menyatakan sama saja antara calon independen dan calon dari partai dan 17 % menyatakan calon gubernur yang ideal berasal dari parpol. Dari hasil polling tersebut dapat kita baca bahwa sebenarnya calon independen cukup diminati masyarakat meskipun banyak pula yang berpendapat baik calon indepeden maupun calon dari partai sama saja. Adapun angka 17 % untuk calon dari parpol kian menegaskan merosotnya citra partai. Penutup Capres Independen merupakan solusi terhadap krisisnya regenerasi kepemimpinan di negeri ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik telah gagal memunculkan regenerasi kepemimpinan nasional yang tangguh. Oleh karena itu calon independen menjadi keniscayaan dalam menjawab problem kepemimpinan. Ada beberapa hal yang penting mengenai calon independen, antaralain: Pertama, bahwa calon independen dapat dipandang sebagai katalisator di tengah kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang kini memiliki citra oligarkis, feodal, dan transaksional. Kedua, pada akhirnya kita mencatat bahwa seorang calon independen harus memiliki modal yang memadai sebelum ikut dalam pertarungan, baik itu modal finansial dan modal politik. Supaya dalam perjalanannya tidak mudah digoyahkan dan benar-benar mampu mengelola harapan publik akan munculnya harapan baru dari calon alternatif yang tidak tersandera partai. Ketiga, masih tersumbatnya kran bagi capres independen untuk berlaga dalam pilpres juga wajib menjadi sorotan kita bersama. Manakala suplai pemimpin nasional masih mutlak harus berasal dari partai sama halnya mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Prinsip setiap warga berhak memilih dan dipilih menjadi jargon semata selama kesempatan bagi capres independen masih disumbat. Kelima,partai politik seharusnya tidak antipati terhadap menculnya calon independen, baik ditingkat daerah maupun nasional. Kahadiran calon independen sudah semestinya dianggap sebagai pematik untuk partai membenahi diri. Juga harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kompetitif dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas. 15 Daftar Pustaka Abbas, Cakra. Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh. Medan: Sofmedia. 2012. Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. Amirudin, Bisri dan Ahmad Zaini. Pilkada Langsung Problem dan Prosepek; Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. Firmanzah. Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010. Firmanzah. Marketing Politik; Antar Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008 Heryanto, Gun Gun. Dinamika Komunikasi Politik. Jakarta: Lasswell Visitama. 2011. Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. Thubany, Syamsul Hadi. Pilkada Bima 2005; Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia. Tuban: Bina Sawigiri. 2005. Surbakti, Ramlan, Mamahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Grasindo, 2006. 16