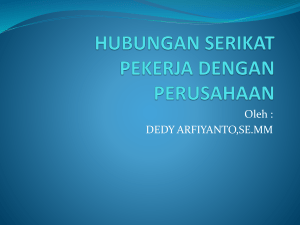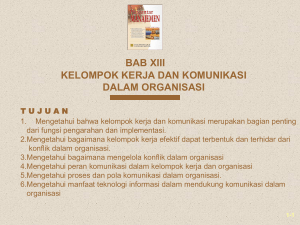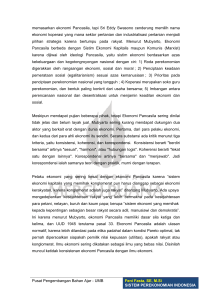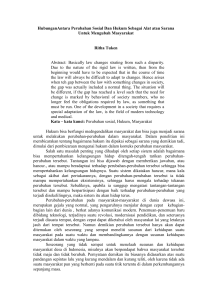bab 8 diskursus dan praktik potensi golongan miskin
advertisement

BAB 8 DISKURSUS DAN PRAKTIK POTENSI GOLONGAN MISKIN Diskursus dan praktik potensi golongan miskin mengoperasikan kekuasaan untuk membuka berbagai akses guna memunculkan tubuh-tubuh miskin. Aksesakses tersebut menjadi modal bagi tubuh miskin untuk menunjukkan potensinya. Mekanisme pembalikan pemikiran dilakukan akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam diskursus dan praktik ini. Pertama, tubuh-tubuh miskin tidak ditenggelamkan dalam penghitungan statistika maupun persangkaan budaya, melainkan justru diajak untuk muncul bersama pendamping. Dalam arena proyek penanggulangan kemiskinan, golongan miskin muncul dalam menentukan subyek kemiskinan sendiri. Kedua, tubuh-tubuh miskin tidak dicurigai, sebaliknya dipercaya untuk memecahkan persoalannya sendiri. Interaksi dalam kelompok mengarahkan munculnya kekuasaan yang menguatkan solidaritas sosial, dan diarahkan untuk mencapai kemandirian golongan miskin itu sendiri. Ketiga, golongan miskin tidak dipandang sebagai Si Lain (Other) melainkan menjadi subyek kemiskinan sendiri, yang biasa disebut sebagai orang dalam. Pe-Lain-an justru diterapkan kepada pihak-pihak di luar golongan miskin, sehingga berkonsekuensi pada tugas orang luar untuk mendekati golongan miskin tersebut –bukan tugas golongan miskin untuk beradaptasi dengan orang luar. Orang luar menjadi diperlukan (penyuluh, pendamping) agar bersamasama mewujudkan potensi golongan miskin menjadi kekuatan/kekuasaan nyata. Potensi hendak dikembangkan setinggi-tingginya, baik dari level individual, kelompok, hingga gabungan kelompok (pada pemikiran peningkatan kapasitas petani, nelayan dan koperasinya), pada level lokal, regional, nasional dan internasional (dalam kegiatan kredit mikro). Diskursus ini memang berkembang melalui seminar dan penerbitan ilmiah, serta jaringan ilmuwan dan aktivis lokal hingga global. Kekuasaan lebih utama dioperasikan sebagai kekuatan untuk meningkatkan solidaritas antar pihak dan antar lapisan sosial –bukan terutama untuk mendominasi pihak lain. Masyarakat sendiri dipandang terstruktur secara 128 hierarkis. Golongan miskin ditentukan pada lapisan terbawah dari masyarakat tersebut. Kekuasaan untuk meningkatkan solidaritas beroperasi ketika agensi dalam struktur tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak antar lapisan sosial. Dibandingkan dengan konsep orang miskin, lebih dikenal konsep golongan miskin, golongan lemah, golongan terbawah dari masyarakat. Subyek kemiskinan mencakup lapisan terbawah dari masyarakat, yang dapat berupa petani berlahan sempit, buruh tani, buruh industri kecil, pengangguran. Namun demikian, karena seringkali menggunakan data individu miskin, dapat diperkirakan bahwa diskursus dan praktik potensi golongan miskin diterapkan pada 13 persen atau 31 juta penduduk miskin di Indonesia. Penyebab jatuhnya mereka pada posisi terbawah ialah ketidaksamaan sosial (social inequality) yang bersumber dari ketidaksamaan akses terhadap berbagai aspek pola nafkah. Tubuh-tubuh tersebut bukanlah miskin dalam makna tidak memiliki barang dan jasa (the have nots), namun disebabkan oleh akses kepada penghidupan yang tidak merata dalam masyarakatnya. Mempercayai Tubuh Miskin Sejarah pemikiran tentang potensi orang miskin menempati posisi penting, karena selama lebih dari dua dekade dikembangkan (1970-an hingga 1980-an) sebelum dioperasikan dalam arena program pemberdayaan masyarakat pada waktu berikutnya (melalui Program IDT/Inpres Desa Tertinggal yang dimulai tahun 1993). Adapun predisposisi yang dikembangkan berupa pemikiran dikotomis berakses-nirakses, dan solidaritas-persaingan (Gambar 11). Diskursus potensi golongan miskin mendeteksi tubuh miskin pada golongan terlemah dalam masyarakat (Sajogyo 1977: 10-17). Tubuh golongan miskin bukan menunjukkan ketiadaan, melainkan masih meninggalkan jejak kepemilikan potensi untuk mandiri. Kemiskinan mereka dimaknai sebagai ketidaksamaan atau kesenjangan (inequality) dari golongan di atasnya (Sajogyo 2006: 261-282). Kesenjangan sosial tersebut menghambat potensi mereka, karena ketiadaan akses untuk berkembang. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan 129 kemiskinan diarahkan untuk memeratakan akses bagi tubuh-tubuh golongan miskin (Supriatna 1997: 24-25). Berakses Solidaritas Kelompok Persaingan Individualistik Nirakses Gambar 11. Dikotomi Diskursus Potensi Golongan Miskin Potensi kemandirian muncul karena dalam tubuh golongan miskin terkandung struktur pengetahuan tersendiri, mampu mengakumulasi pengetahuan, terutama perihal mekanisme menjadi miskin dan untuk lepas dari kemiskinan. Konsekuensinya, tubuh golongan miskin dapat dipercaya untuk mengkaji dan memahami kemiskinan di sekelilingnya serta memahami mekanisme untuk lepas dari kemiskinan. Mubyarto (1997: 3) mempraktikkannya dalam Program IDT. Filsafat yang mendasari pendekatan Program IDT adalah mempercayai penduduk miskin, bahwa apabila dibantu secara tepat mereka akan dapat "mengentaskan diri" dari kemiskinan yang mereka alami. Maka Program IDT ditekankan sebagai program pemberdayaan yang diarahkan pada upaya-upaya memperkuat dan memampukan usaha-usaha ekonomi rakyat dalam mencapai kemandirian. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan sekaligus pemasaran, terutama yang sumberdayanya tersedia setempat dan dikerjakan oleh rakyat secara swadaya. Kepercayaan kepada tubuh golongan miskin diwujudkan dengan membuka akses partisipasi mereka dalam kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam proses partisipasi tersebut, berbagai posisi sosial yang berbeda 130 hierarkinya diharapkan saling bekerjasama. Tindakan kerjasama ini mencipta solidaritas antar posisi sosial. Bagaimanapun kunci keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan adalah pada sikap keberpihakan aparat pemerintah atau birokrasi pada ekonomi rakyat dan penduduk miskin yang terlibat di dalamnya. Meningkatkan kepedulian, keberpihakan, dan komitmen warga yang tidak miskin terhadap warga yang masih hidup serba kekurangan hendaknya terus menerus kita dorong (Mubyarto 1997: 20). Berkaitan dengan hubungan antar pihak, dalam diskursus ini dioperasikan praktik metode partisipatoris, atau kadang-kadang dinyatakan sebagai metode partisipatif. Metode ini menyalurkan kekuasaan untuk menghubungkan berbagai pihak yang berbeda posisi sosial, sehingga sekaligus mengembangkan solidaritas antar pihak. Dalam metode partisipatoris berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda saling berinteraksi sampai menghasilkan keputusan bersama. Warga desa turut berpartisipasi dalam menganalisis kondisi lingkungan mereka sendiri, dengan cara menyumbang gagasan dan kritik (Mubyarto 1996: 8). Metode lainnya ialah belajar dan bertindak bersama (Participatory Learning and Action). Dalam metode ini warga miskin dipandang kreatif dan mampu menganalisis serta merencanakan hidupnya sendiri (Mubyarto 1996: 7). Orang luar hanyalah berperan sebagai penyelenggara, katalis, atau pemelancar. Metode kajian bersama (co-operative inquiry) juga bersesuaian dengan diskursus ini, karena memandang setiap pribadi memiliki kemampuan untuk bertingkah laku mandiri (Mubyarto 1996: 7). Oleh sebab itu setiap pihak yang terlibat dalam kajian bersama dipandang sama-sama sebagai peneliti. Sumber pengetahuan dan instrumennya ialah semua pihak yang terlibat langsung. Secara spesifik, pengetahuan tersebut diperoleh dari tatap muka, hasil praktik, pengalaman, dan yang dipresentasikan. Secara rinci metode partisipatoris sebagai proses pengembangan solidaritas antar pihak dilaporkan Sajogyo (1997: 114-116). … kajian bersama … telah menghasilkan kesadaran bersama yang semakin kuat akan pentingnya kebersamaan dalam mencari cara dan pendekatan yang lebih sesuai maksud pemberdayaan penduduk dalam menanggulangi kemiskinan. 131 … kajian bersama … mencairkan kekakuan komunikasi dan hubungan antarunsur penggerak pembangunan. … metode ini memiliki dayaguna praktis dalam proses pengembagan program-program yang melibatkan banyak pihak… kajian terbuka semacam ini jarang atau belum pernah dilaksanakan dalam pengembangan suatu program. Metode kajian bersama dianggap mampu untuk membangun suatu jembatan yang kukuh bagi tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sukarela (LSM) yang masing-masing mempunyai pijakan berbeda dalam memecahkan persoalan pengembangan masyarakat. … komunikasi yang lebih intensif antartiga pihak menjadi suatu tuntutan di masa depan untuk menemukan pola-pola hubungan yang lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai tujuan bersama, suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agensi dari lapisan atas yang telah mengembangkan diskursus potensi orang miskin terutama akademisi, yang memiliki pemikiran alternatif untuk pembangunan, seperti pembangunan alternatif, pembangunan partisipatoris, model kebutuhan manusia. Di samping percaya kepada orang miskin dan mengakui solidaritas lintas lapisan sosial, penganut diskursus ini mendeteksi kekuasaan dalam memeratakan hasil pembangunan sebagai mekanisme penting untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerataan sempat terumuskan dalam kerangka delapan jalur pemerataan plus empat jalur tambahan. Dua jalur pembuka pemerataan ialah peluang berusaha dan peluang bekerja. Keduanya menentukan tingkat pendapatan (pengusaha, buruh beserta rumahtangga tanggungan), tingkat pangan, sandang, perumahan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pelayanannya terjangkau. Tiga jalur pemerataan lainnya dimatrikskan dengan kelima jalur terdahulu, yaitu meliputi jalur peranserta, jalur pemerataan antardaerah kota dan desa, serta kesamaan dalam hukum. Empat jalur tambahan yang perlu diwujudkan terlebih dahulu berupa pemerataan pola penguasaan tanah, pola penyediaan modal usaha bagi masyarakat, pola komunikasi pengetahuan baru bagi pengusaha dan buruh, serta pola penyediaan input baru untuk usaha yang makin banyak berasal dari luar desa. (Sajogyo 2006: 203-206), Telah dikembangkan pula pemikiran moral ekonomi Pancasila (Mubyarto 1987: 53). Sistem ekonomi ini bercirikan penggerak perekonomian berupa rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Penggerak lainnya ialah kehendak untuk 132 pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Kebijakan ekonomi diprioritaskan kepada penciptaan perekonomian nasional yang tangguh atau nasionalisme ekonomi. Dalam kaitan ini, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian yang kongkrit. Untuk mengembangkan keadilan sosial, diperlukan pula imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Setelah krisis moneter, Mubyarto juga mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ini mencakup sistem perekonomian tradisional yang telah dikerjakan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun (Mubyarto 1996: 46). Sistem ini bercirikan penggunakan teknologi sederhana dengan pemanfaatan tenaga kerja dari dalam keluarga. Segala aspek di dalamnya tidak dilihat sebagai keterbelakangan, melainkan sebagai strategi lokal untuk mengatasi masalah setempat. Agensi lain dari lapisan atas yang berperan penting dalam diskursus ini ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Identitas swadaya dalam organisasi ini lebih menunjukkan kemandirian, sambil menurunkan identitas sebagai organisasi kontra pemerintah (Ismawan 1996: 49-53). Sebagian akademisi sekaligus menjadi aktivis LSM, yang berarti sekaligus memerankan penyusunan pengetahuan formal kemiskinan dan praktik penanggulangannya. Predisposisi pemerataan akses dapat menjadi dorongan bagi praktik pemberdayaan, seperti pemberian fasilitas, pelatihan penggunaannya, dan penyusunan pengetahuan bersama-sama antara pihak luar dan golongan miskin. Pemberdayaan menjadi saluran untuk meningkatkan akses berbagai aspek produktif bagi golongan miskin. Dalam pemberdayaan, tubuh miskin diakui rasionalitasnya, kebijakan lokalnya, apresiasinya terhadap alam, dan perilaku mereka lainnya (Mubyarto 1996: 7-8). Orang luar justru belajar untuk menghargai hal itu, sehingga diharapkan untuk berdialog serta tidak bertindak tergesa-gesa dan menggurui. Meskipun diyakini munculnya peluang solidaritas untuk menghubungkan berbagai posisi sosial, disadari pula persoalan interaksional antara orang luar dan orang dalam (Siregar 2001: 366-397). Berorientasi pada golongan miskin, identitas mereka didefinisikan sebagai orang dalam. Kerjasama dari orang luar bertujuan memunculkan penyadaran dan rasa kepemilikan orang dalam terhadap 133 masukan kegiatan dan program dari luar (Mubyarto 1995: 18-22). Dengan kata lain, interaksi sosial tersebut diarahkan pada proses sosial berupa kerjasama, dan pelembagaan (institutionalization) sampai masukan dari luar dirasakan sebagai milik tubuh golongan miskin. Siregar (2001: 370-372) menuliskan pengalamannya. … pendampingan merupakan ruang dialog antara dua ranah budaya yang saling membuka diri untuk berubah, saling berbagi, dan saling mempengaruhi, yaitu antara OL (Orang Luar) dan OD (Orang Dalam). Pengertian saling-berubah di situ tidaklah terbatas pada perubahan gagasan (teori dan kebijakan), melainkan juga cara pandang dan watak kami sebagai OL terhadap beragam gejala dan fakta….. Akhirnya, kami menyadari bahwa lebih dari apapun, kesuksesan menjalin pertemanan dengan OD lebih banyak ditentukan oleh kesediaan kami belajar mempraktikkan, melakoni, menghayati, dan menikmati proses belajar dan bertindak bersama masyarakat. Kami lebih banyak menerima ketimbang memberi. Pada golongan miskin sendiri dikembangkan proses kerjasama atau solidaritas, dalam bentuk pembentukan kelompok. Melalui proses sosial tersebut anggota yang lebih mampu dapat membantu anggota yang lebih kekurangan (Mubyarto 1995: 11). Kelompok menjadi atribut penting bagi tubuh golongan miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya diarahkan untuk memandirikan tubuh golongan miskin, namun juga pada kelompok golongan miskin (Sajogyo 1997: 109-110). Dalam berinteraksi dengan kelompok tubuh miskin sehari-hari, orang luar berperan sebagai pendamping kelompok. Pada saat interaksi dalam kelompok lemah atau tanpa kegiatan, pendamping merangsang tubuh-tubuh miskin untuk menciptakan kegiatan sendiri. Pada saat anggota kelompok telah aktif menjalankan kegiatannya, pendamping menyediakan akses kepada peningkatan kemampuan modal ekonomi, pengetahuan, ketrampilan. Pendamping menjadi mitra kerja kelompok tersebut, sehingga pendampingan dinilai sebagai profesi yang berlangsung secara berkelanjutan, dan dapat diarahkan menjadi pendampingan yang mandiri. Pendamping tidak dipandang sebagai unsur yang terpisah dari program penanggulangan kemiskinan, melainkan integral yang hidup 134 dari mekanisme hubungan dengan kelompok masyarakat yang didampinginya (Sajogyo 1997: 13). Dengan melekatnya pendamping, maka kelompok tidak harus mulai dikembagkan dari anggota yang sudah mampu. Pendamping justru berperan menyesuaikan persyaratan arena kelompok dengan habitus anggota, atau melatih anggota sehingga habitusnya sesuai dengan arena kelompok. Peran minimal dari pendamping ialah memastikan komponen program (pengembangan kelompok masyarakat, penyaluran dana) tetap lestari dan, bila memungkinkan, berkembang lebih lanjut. Keberlanjutan tersebut mencakup kelembagaan dan administrasi kelompok yang meningkat, serta peningkatan jumlah dana yang dikelola. Hal ini disampaikan Sajogyo (1997: 134-136). Dalam rangka Microcredit Summit di Washington pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 1997, yang hendak mengentaskan 100 juta keluarga dari kemiskinan pada tahun 2005, Indonesia mentargetkan untuk mengentaskan tujuh juta keluarga atau sekitar 28 juta orang miskin. Melalui pendekatan kelompok dan pengembangan kelembagaan pendampingan, program penanggulangan kemiskinan tujuh juta keluarga miskin itu berarti akan membentuk sekitar 280.000 pokmas, melibatkan 11.200 tenaga pendamping, 2.240 koordinator kecamatan dan 2.240 tenaga administrasi dan tergabung dalam Lembaga Pendamping Kelompok (LPK). Untuk mengoperasikan 2.240 LPK itu dibutuhkan dana Rp 138 miliar per tahun (2.240 x Rp 61.875.000)… Jumlah tersebut masih perlu ditambah dengan biaya-biaya penyiapan bagi pembentukan atau pengembangan LPK di seluruh Indonesia sebesar kurang lebih Rp 12 miliar. Sementara itu, dana yang harus dimobilisasi untuk kepentingan pengembangan usaha adalah Rp 1,225 triliun per tahun atau kurang lebih Rp 6 triliun selama lima tahun. Dari jumlah biaya sebesar Rp 138 miliar rupiah, diasumsikan akan memerlukan 5 tahun untuk mencapai tingkat keuntungan, dengan rincian kemampuan pembiayaan (cost recovery) sebagai berikut: - Tahun I mampu membiayai : 10% - Tahun II mampu membiayai : 20% - Tahun III mampu membiayai : 40% - Tahun IV mampu membiayai : 60% - Tahun V mampu membiayai : 80% - Tahun VI mampu membiayai : 120% (untung) 135 Berkelompok Menghadirkan Kekuasaan Setelah melalui kajian akademis sejak tahun 1970-an, dan pendampingan melalui LSM sejak 1980-an, mulai tahun 1993 diselenggarakan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Mubyarto, akademisi penganut diskursus potensi golongan miskin mengembangkan desain program IDT tersebut. Berkompromi dengan aparat pemerintah, konsep kelompok swadaya masyarakat (KSM) diputuskan menjadi kelompok masyarakat (pokmas). Penghilangan konsep swadaya dipandang sebagai pelarangan pembangunan yang sepenuhnya bottom-up (Sajogyo 1997: 13, 122-123). Sampai mana upaya sejumlah LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang tahun 1993 itu menunjukkan kepedulian berhasil "menjual" konsep dana bergulir dalam kelompok pada pemerintah dalam rangka "peningkatan penanggulangan kemiskinan" (istilah di buku Repelita waktu itu)? Singkat saja: LPSM secara resmi tak pernah dimintai bantuannya, dari mulai awal penggodokan konsep program maupun dalam pelaksanaannya di daerah. Di dalam program IDT yang dimulai tahun 1994 pemerintah pusat memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sesuai undangundang berlaku maupun kebijakan sentralistik sama sekali tanpa menyebut peranan LPSM. Di pusat pemeran utama adalah Bappenas dan Departemen Dalam Negeri, Dirjen PMD khususnya. Bahkan pemerintah menunjukkan kelainannya dalam hal penamaan kelompok dibentuk keluarga miskin yang menerima dana bergulir itu. Nama yang diacu LPSM adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), tapi yang dipakai oleh Program IDT adalah pokmas, yaitu Kelompok Masyarakat, tanpa kata "swadaya": gambaran sikap "jangan pakai nama dari kamus LPSM"? (Sajogyo 2006: 179). Program ini melakukan berbagai pembalikan pemikiran utama pada masanya. Tubuh miskin yang sebelumnya dimaknai secara negatif kini diberi kepercayaan penuh, sejak penentuan siapa sajakah orang miskin di wilayahnya, turut serta dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan secara mandiri, hingga mengevaluasi hasil kegiatan (Bappenas Tt: ii). Dibandingkan dengan nilai dana bantuan desa tahunan saat itu sebesar sekitar Rp 6 juta, nilai program IDT 136 sebesar Rp 20 juta per desa berarti bernilai tiga kali lipat. Dana yang dinilai sangat besar itu sepenuhnya dikelola pokmas yang berisikan tubuh-tubuh miskin. Setiap pokmas mendapatkan sejumlah dana, biasanya senilai Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta per anggota, dan satu kelompok beranggotakan maksimal 20 orang. Dalam satu desa dapat terbentuk banyak pokmas. Setelah tahun pertama, dana pengembalian dari anggota digulirkan kepada anggota lainnya, atau digulirkan kepada pokmas lainnya. Untuk menciptakan solidaritas di antara anggotanya, diciptakan aturan tanggung renteng, di mana kesulitan pengembalian oleh satu anggota turut ditanggung bersama anggota lainnya. Di samping partisipasi tubuh miskin untuk menentukan warga desa lain yang setara dengannya, di tingkat nasional kemiskinan dipatok menurut garis kemiskinan. Di Indonesia, Sajogyo (1988: 1-14; 2006: 247-259) mula-mula mengembangkan garis kemiskinan untuk menentukan jumlah individu miskin sejak tahun 1977, sebelum akhirnya pemerintah secara resmi menggunakan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai tahun 1984. Garis kemiskinan Sajogyo dan BPS sama-sama disusun menurut nilai gizi minimal setara 2.100 Kkal per orang dalam sehari, namun demikian terdapat perbedaan rincian dalam penyusunannya. Menurut Sajogyo (1988: 1-14), pada saat diterapkan pada masyarakat simpangan datanya menurun hingga dua deviasi standard, sehingga masih bisa ditoleransi hingga 1.900 Kkal per orang-hari. Adapun proses pengumpulan data gizi dengan menggunakan pendekatan ingatan (recall) seringkali terlapor lebih rendah (under reporting) hingga 20 persen. Atas dasar pengalaman ini, maka garis kemiskinan terbawah dapat ditoleransi hingga 1.700 Kkal per orang-hari. Untuk menghasilkan pengukuran yang lebih realistis, sesuai peluang keragaman kemiskinan antar daerah, Sajogyo menyusun garis kemiskinan lebih dari satu agar kian tajam mengukur kemajuan golongan bawah. Dirumuskannya garis melarat (destitute), miskin sekali (very poor), dan miskin (poor). Berdasarkan nilai tukar beras, dibedakan pula garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di desa dipancang garis 180 kg, 240 kg, dan 320 kg setara beras per orang-tahun. Untuk kota nilainya 270 kg, 360 kg, dan 480 kg setara beras per orang-tahun. Demi kepraktisan, nilai rupiah bagi kalori lalu dipertukarkan dengan 137 nilai beras. Beras mudah dipahami sebagai sumber kalori dan harganya tidak fluktuatif. Sejak awal penentuan desa tertinggal untuk menjaring tubuh-tubuh golongan miskin dipertanyakan. Tidak terdapat korelasi yang kuat antara lokasi tertinggal dan permukiman golongan miskin (Sarman 1997: 33-42). Sesuai dengan data kemiskinan dari BPS, jumlah tubuh orang miskin dalam satu provinsi atau satu kabupaten diprediksi melalui Survai Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), bukan berupa sensus. Desa tertinggal, sementara itu, ditentukan dari susunan variabel sensus Potensi Desa (Podes). Sebagai ganti kesulitan menentukan jumlah orang miskin dalam satu desa melalui Susenas–dan sesuai dengan orientasi kepercayaan kepada golongan miskin—tubuh-tubuh miskin di tiap desa akhirnya ditentukan oleh warga desa sendiri (Mubyarto 1997: 3). Tubuh miskin juga dipercaya untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sendiri. Dalam salah satu survai untuk mengevaluasi pokmas IDT, diketahui bahwa hanya seper tiga pokmas tersebut mandiri (Sajogyo 1997: 13, 122-123). Yang menarik, selain ditemukan pokmas yang telah mandiri, juga ditemukan tubuh anggota pokmas yang telah melepaskan identitas miskin dan sedang berkembang lebih lanjut. Sayangnya, Program IDT tidak mengantisipasi tubuh usahawan baru hasil berkelompok, namun me-Lain-kannya dengan sekedar mengeluarkannya dari pokmas asal. Tidak tersusun rencana pendampingan lebih lanjut untuk anggota pokmas yang telah mandiri, atau pengembangan jaringan permodalannya dengan perbankan. Berbeda dari tataran diskursus yang berminat mengembangkan potensi golongan miskin setinggi-tingginya, ternyata tataran arena program penanggulangan kemiskinan telah membatasi diri pada pengembangan potensi sekedar sampai keluar dari kemiskinan. Kejanggalan muncul saat metode penanggulangan kemiskinan yang memerlukan kemitraan dari seluruh pihak di lokasi tertentu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pendamping dalam program IDT mampu bermitra dengan tubuh miskin. Akan tetapi kemitraan sulit dijalin bersama pemerintah daerah, swasta dan LSM. Hal ini tecermin dalam kajian bersama Program IDT (Mubyarto 1996: 26). 138 Di sebagian pertemuan sarasehan keterpaduan PPK (Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan) yang diadakan atas usulan Tim Jisam (Kajian Bersama) P3R-YAE, di tingkat I maupun di tingkat II, diperoleh sejumlah apresiasi atas pendekatan (metode) diskusi kajian bersama yang terarah (terfokus), dalam situasi duduk sama rendah berdiri sama tinggi itu di antara peserta diskusi. Disayangkan, tidak seluruh peserta pada diskusi awal (arus turun) dapat berperan serta pada diskusi kedua (arus naik) ketika Tim Jisam Pusat P3R-YAE membawakan hasil jisam dari desa dan kecamatan kasus, sehingga dampak kumulatif tak sepenuhnya tercapai. Begitu pula ketidakhadiran unsur swasta (pengusaha) dan unsur LSM/Ormas sebagai peserta diskusi jisam dirasakan sebagai suatu kekurangan dalam proses menyertakan seluas mungkin unsur-unsur yang kepeduliannya sangat diharapkan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa kasus. Pemrograman menuju pendamping mandiri juga praktis berhenti. Hingga saat ini dapat dijumpai tubuh-tubuh pendamping di tingkat kecamatan hingga provinsi yang semula dilekati label pendamping IDT. Akan tetapi upaya pengembangan profesi berlangsung secara individual, tidak terencana dalam suatu program penanggulangan kemiskinan. Menurunnya diskursus potensi golongan miskin dalam program nasional penanggulangan kemiskinan masa kini telah menenggelamkan pernyataan-pernyataan kemandirian pendamping. Ikhtisar Dengan mempercayai potensi tubuh miskin untuk berkembang menuju kemandiriannya, diskursus potensi golongan miskin memunculkan mereka, lallu pendamping mengajaknya mengembangkan kekuasaan melalui kelompok dan usaha ekonomis. Kekuasaan beroperasi melalui aktivitas pemerataan akses modal usaha, akses prasarana ekonomis dan pendampingan. Dalam konteks demikian, tubuh miskin menjadi orang dalam sementara pendamping dan pihak lain berposisi sebagai orang luar. Hubungan keduanya mengoperasikan kekuasaan untuk menciptakan permukaan solidaritas antar pihak dan antar lapisan sosial. Pada bab berikutnya hendak dikemukakan diskursus dan praktik kemiskinan produksi. Menggunakan arena yang serupa dengan praktik potensi golongan miskin–meskipun saling dimanipulasi—ada baiknya dikemukakan 139 pembedaan, di mana diskursus potensi golongan miskin mengoperasikan kekuasaan dalam upaya memunculkan tubuh miskin terus menerus, sementara diskursus kemiskinan produksi menenggelamkan kembali tubuh miskin dalam mekanisme arena birokrasi ciptaan lapisan atas.