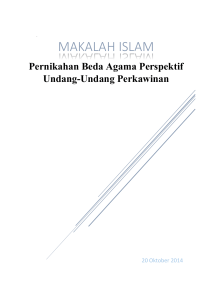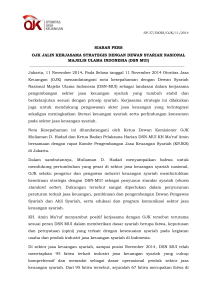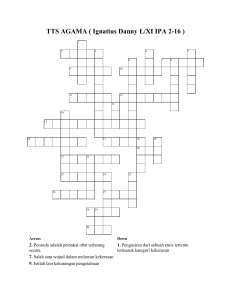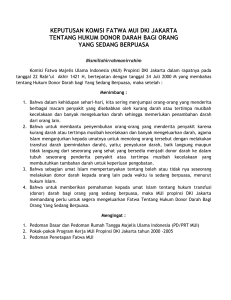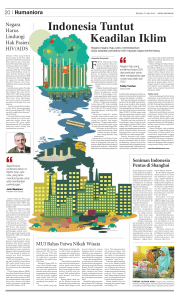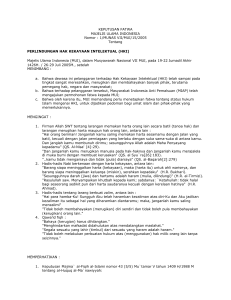kertas kerja majlis muzakarah ulama mabims bioetika dan
advertisement

KERTAS KERJA MAJLIS MUZAKARAH ULAMA MABIMS BIOETIKA DAN PEMBANGUNAN PERUNDANGAN ISLAM SERANTAU FATWA-FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) MENGENAI MASALAH-MASALAH BIOETIKA TAHUN 1975 – 20111 2 - Mohamad Atho Mudzhar , Indonesia Bismillahirrohmanirrohim. PENDAHULUAN Bioetika adalah studi mengenai implikasi etik dan moral daripada temuan-temuan baru dalam ilmu biologi dan kemajuan-kemajuan baru dalam ilmu biomedika, seperti dalam hal rekayasa genetika dan penelitian obat-obatan (Bioethics is the study of ethical and moral implications of new biological discoveries and biomedical advances, as in the fields of genetic engineering and drug research). Definisi lain mengatakan bahwa bioetika ialah studi mengenai problem-problem etika yang muncul dari penelitian-penelitian biologi dan penerapannya dalam bidang-bidang seperti transplantasi organ tubuh manusia, rekayasa genetika, atau inseminasi buatan (Bioethics is the study of ethical problems arising from biological research and its application in such fields as organ transplantation, genetic engineering or artificial insemination). Dikatakan bahwa bioetika itu berkaitan erat dengan isu-isu social, agama, ekonomi, dan hukum, bahkan juga politik. Biasanya ada tiga bidang kajian bioetika, yaitu: pertama, bidang medis seperti soal aborsi, eutanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi buatan, dan rekayasa genetika; kedua, bidang pemeliharaan kesehatan manusia seperti hak-hak pasien, budaya kesehatan masyarakat, moralitas penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan lain-lain; dan ketiga, bidang yang terkait dengan hak-hak hidup hewan terutama yang dijadikan obyek penelitian. Dalam ilmu kedokteran biasanya dikenal ada empat kaedah dasar moral dan etika kedokteran yaitu beneficence 1 Makalah ini disajikan pada Muzakarah Ulama MABIMS dengan tema Bioetika dan Pembangunan Perundangan Islam Serantau, diselenggarakan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, tanggal 17 Nopember 2012 di Singapura. 2 Professor of Sociology of Islamic Law at the Faculty of Shariah and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia juga menjabat sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas yang sama. 1 (dokter berbuat untuk kesembuhan maksimal pasien), non-maleficence (tidak boleh ada perbuatan dokter yang merugikan kesehatan pasien), justice (berlaku adil terhadap semua pasien yang ada), dan outonomy (pasien diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan memutuskan mengenai tindakan medic terbaik bagi dirinya). Majlis Ulama Indonesia (MUI) sejak berdirinya pada tahun 1975 hingga tahun 2011 telah mengeluarkan kurang lebih delapan fatwa yang dapat dikategorikan sebagai fatwa diseputar persoalan bioetika yaitu fatwa-fatwa tentang wasiat menghibahkan kornea mata, bayi tabung atau inseminasi buatan, pengambilan dan penggunaan katup jantung, cloning, penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan obatobatan dan kosmetika, penggunaan mikroba dan produk mikorobial dalam produk pangan, transfer embrio ke rahim titipan, serta bank mata dan organ tubuh lain.3 Makalah ini hendak mencoba menganalisis dua saja diantara fatwa-fatwa itu yaitu fatwa mengenai pengambilan dan penggunaan katup jantung dan fatwa mengenai aborsi. Analisis itu akan melihat kekuatan dalil-dalil hukum agama Islam yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut dan bagaimana serta sejauhmana masyarakat dan pemerintah Indonesia telah meresponi masalah-masalah itu dalam perundangan-undangan Indonesia. SEKILAS SEJARAH MAJLIS ULAMA INDONESIA Majlis Ulama Indonesia (MUI) dideklarasikan pendiriannya oleh sebanyak 53 orang ulama dari seluruh Indonesia pada tanggal 27 Juli 1975. Para ulama itu baru saja selesai menghadiri sebuah Muktamar Ulama di Jakarta yang disponsori oleh pemerintah Suharto dengan bekerjasama dengan tiga orang tokoh ulama Indonesia terkemuka yaitu H. Sudirman, Buya Hamka, dan KH Abdullah Syafi’i. Para ulama yang duduk dalam kepemimpinan MUI Pusat itu mewakili kelompok ulama konservatif yang biasa tergabung dalam Nahdatul Ulama (NU) dan ulama modernis yang biasa tergabung dalam Muhammadiyah, disamping perwakilan ulama independen (non-Ormas) dan Ormas lainnya seperti Persis dan Al-Washliyah. 3 Lihat K.H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, diterbitkan oleh Sekretariat Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, 2011. 2 Pada awalnya ide pendirian MUI itu ditentang oleh masyarakat Islam, karena dikhawatirkan akan digunakan oleh pemerintah Suharto untuk “mengebiri” (“castratory”) umat Islam. Tetapi kemudian masyarakat Islam menerima saran pendirian MUI itu dan Buya Hamka bersedia menjadi ketua Umum pertama MUI dengan pertimbangan untuk mempersatukan umat Islam dan untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam dan menjaga ideologi bangsa Indonesia Pancasila (Five Principles). Dalam bentuknya sekarang, terdapat MUI Pusat pada tingkat nasional di Jakarta, kemudian terdapat cabang-cabangnya di setiap propinsi (provinces), kabupaten/kota (districts/manucipalities), dan kecamatan (sub-districts) di seluruh Indonesia. MUI Pusat memiliki sebuah unit organisasi bernama Komisi Fatwa (Fatwa Committee) yang tugasnya ialah membahas masalah-masalah hukum Islam aktual dalam masyarakat atau merespon pertanyaan-pertanyaan hukum Islam dari masyarakat. Setelah masalah itu dikaji dan ditemukan hukumnya menurut hukum Islam, lalu hasil istinbat hukum Komisi Fatwa itu diumumkan oleh MUI sebagai fatwa MUI. Terkadang sebagian fatwa MUI juga bukanlah hasil keputusan Komisi Fatwa MUI melainkan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tahunan MUI yang pesertanya lebih luas yang terdiri atas seluruh perwakilan MUI di Indonesia. Kemudian sejak tahun 1999 MUI juga membentuk sebuah unit bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang tugasnya khusus mempelajari dan menjawab pertanyaan masalah-masalah hukum Islam yang berhubungan dengan ekonomi Islam atau di Indonesia disebut ekonomi Syariah). Hasil istinbat hukum DSN ini kemudian diumumkan juga sebagai fatwa MUI. Sejak berdirinya pada tahun 1975 itu hingga tahun 2011 (melalui Komisi Fatwa dan Mukernas) MUI telah mengeluarkan sebanyak 180 fatwa, kemudian melalui DSN sebanyak 80 fatwa. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kurang lebih delapan dari fatwa-fatwa itu dapat dikategorikan ke dalam fatwa mengenai masalah-masalah bioetika. 4 4 Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah MUI, lihat Mohamad Atho Mudzhar, FATWA-FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA; SEBUAH STUDI TENTANG PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, 1975-1988, Penterbit Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1993. Untuk daftar fatwa DSN-MUI, lihat H. M. Ichwan Sam, et al, HIMPUNAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL INDONESIA, edisi revisi, diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Jakarta, 2006. 3 FATWA PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG Fatwa mengenai pengambilan dan penggunaan katup jantung (heart-valve transplantation) dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 29 Juni 1987. Fatwa itu mengatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal dunia untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya. Fatwa ini berisi dua hal, pertama pengambilan katup jantung orang yang telah mati (berarti berhubungan dengan hukum pembedahan mayat atau outopsi), dan kedua penanaman katup jantung itu kepada orang lain yang masih hidup (transplantation). Fatwa ini secara konsisten menggunakan kata-kata “katup jantung” (heart valve) dan tidak menggunakan kata “jantung” (heart) saja. Fatwa itu dikeluarkan MUI sebagai respon terhadap surat yang berisi pertanyaan dari seorang kepala Bagian Bedah Jantung dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta Nomor 03/BJ/85 tertanggal 11 Desember 1985. Fatwa itu dikeluarkan setelah Komisi Fatwa MUI mendengarkan uraian Dr. Tarmizi Hakim, Kepala Bagian Bedah Jantung Rumah Sakit “Harapan Kita” Jakarta mengenai teknis pengambilan dan penggunaan katup jantung pada tanggal 16 Mei 1987; dan juga setelah mendengarkan pembahasan para anggota Komisi Fatwa dalam beberapa kali sidangnya, terakhir pada tanggal 27 Juni 1987. Ada tiga macam dalil yang menjadi landasan MUI untuk mengeluarkan fatwa itu yaitu dalil Al-Quran, Al-Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab yang dianggap mu’tabarah. Adapun dalil dari ayat Al-Quran yang dijadikan landasan fatwa itu ialah ayat-ayat Al-Quran yang secara umum menyuruh berbuat baik terhadap sesama manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”(QS Al-Maidah ayat 2). Juga Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: “...Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS Al-Baqarah ayat 195). 4 Adapun dalil dari hadis Nabi ialah berupa tuntunan Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk mencari kesembuhan atau berobat apabila sedang ditimpa sakit. Dalam sebuah hadis Riwayat Hakim Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan (pula) obat untuknya.”(HR Al-Hakim). Hadis lainnya yang dikutip ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya mengatakan: “Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah SWT.”(HR Muslim). Setelah itu fatwa tersebut mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kemuliaan kedudukan manusia yang wajib dihormati dan diperlakukan secara baik dan terhormat, baik sewaktu manusia itu masih hidup mapun setelah mati. Ayat Al-Quran yang dikutip itu ialah Surat AlIsra ayat 70 yang artinya: “Sesungguhnya kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam (umat manusia). Kami telah angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami memberi kelebihan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS Al-Isra ayat 70). Fatwa itu kemudian merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan “Memecahkan/merusak oleh Abu tulang Dawud orang yang yang telah mengatakan mati sama (artinya): dengan memecahkan/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup.” (HR Abu Dawud). Selepas itu fatwa tersebut merujuk kepada sebuah kaidah hukum (kaidah fiqhiyah) yang mangatakan (artinya): “Kehormatan orang yang masih hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal dunia.” Selepas itu lagi fatwa tersebut merujuk kepada pendapat para ulama mengenai hukum bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telah meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, seperti disebutkan dalam kitab SHARH AL-MUHADHDHAB (Juz V halaman 300) yang berbunyi: “Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang lain dan pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya.” Kemudian fatwa itu juga mungutip pendapat ulama yang sama dalam buku yang sama (Juz V halaman 301) yang mengatakan (artinya): “Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibedah. 5 Karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian kebolehannya itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat.”5 Setelah menguraikan semua dalil tersebut di atas maka sampailah fatwa itu kepada kesimpulannya atau hasil ketetapan hukumnya sebagaimana telah disebutkan dimuka yaitu bahwa pengambilan katup jantung dari orang yang sudah mati untuk digunakan kepada orang yang masih hidup itu boleh hukumnya, jika tidak ada cara lain yang lebih baik daripada cara itu dan jika telah diwasiatkan oleh si mayit semasa hidupnya serta disaksikan oleh ahli waris terdekatnya. Dari segi tariqah al-istinbat, fatwa itu telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kaedah hukum, dan terakhir pendapat ulama terdahulu. Meskipun fatwa itu tidak menerangkannya secara khusus, wajh al-dilalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang dikutip itu kiranya cukuplah jelas. Adapun mengenai Ijma’ dan Qiyas, tidaklah disebutkan secara explicit dalam fatwa itu. Fatwa itu hanya menyebutkan sebuah kaedah hukum (legal theory) yang biasanya digunakan oleh kebanyakan ulama. Di sini mungkin dapat pula dikatakan bahwa Ijma yang dirujuk oleh fatwa itu bukanlah Ijma’ tentang hukum sesuatu (hukum fiqh), tetapi Ijma’ mengenai prinsip atau teori hukum yang digunakan. Demikian pula prosedur Qiyas tidak diuraikan dan tidak dilakukan dalam fatwa ini, karena persyaratan qiyas adalah menganalogikan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah lain yang telah disebutkan hukumnya dalam nass. Adapun apa yang dilakukan oleh fatwa ini ialah menganalogikan sesuatu hukum yang belum jelas kepada masalah lain yang telah diijtihadkan hukumnya oleh ulama terdahulu. Ini tidaklah disebut Qiyas, tetapi dalam wacana hukum MUI disebut Ilhaq, suatu konsep yang diambil dari tradisi NU di Indonesia. Dalam tradisi NU yang kemudian juga diadopsi oleh MUI, ada tiga cara berijtihad yaitu Qauli (dengan mengutip pendapat ulama terdahulu yang disebutkan dalam sebuah buku/kitab), Ilhaqi (dengan menganalogikan hukum masalah baru yang belum ada hukumnya dengan hukum hasil ijtihad ulama terdahulu, bukan nass, mengenai soal lain yang mirip karaktristiknya), dan Manhaji (bersifat metodologis dengan mengikuti urut-urutan langkah dimulai dengan mencari jawaban masalah itu dalam Al-Quran, dalam hadis 5 Lihat K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, pp. 619-622. 6 Nabi, kemudian dalam Ijma’, dan Qiyas). Kebanyakan fatwa ulama NU dan MUI bersifat Qauli dan Ilhaqi. FATWA PENGGUGURAN KANDUNGAN ATAU ABORSI Fatwa MUI mengenai aborsi sudah tiga kali dikeluarkan. Fatwa yang satu menyempurnakan atau menjelaskan fatwa yang lainnya. Fatwa aborsi yang pertama dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1983. Ketika itu MUI menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama khusus membahas masalah-masalah kependudukan (demographic issues), kesehatan (health), dan pembangunan (development). Salah satu bahagian dari keputusan Musyawarah itu mengenai kesehatan ialah mengenai keluarga berencana (family planning) yang antara lain mengatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau Internal Utarine Devices (IUD) dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau bila terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain, sedangkan family planning dengan vasektomi dan tubektomi adalah haram hukumnya. Haram pula hukumnya melakukan pengguguran kandungan atau aborsi dengan cara apaun, termasuk MR (menstrual regulation), baik dikala bayi sudah bernyawa ataupun belum bernyawa, karena perbuatan itu merupakan pembunuhan manusia secara terselubung kecuali dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad telah dikutip sebagai landasan bagi fatwa itu, tetapi isinya bersifat umum saja karena tema Munas itu memang amat luas yaitu tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.6 Fatwa aborsi yang kedua dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2000, diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI keenam tahun 2000. Fatwa itu dikeluarkan dengan alasan karena di tengah-tengah masyarakat muncul pro dan kontra mengenai hukum melakukan aborsi sebelum peniupan ruh (nafkh al-ruh). Fatwa itu mengatakan mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1983 dan menegaskan lagi bahwa melakukan aborsi sesudah nafkh al-ruh hukumnya ialah haram, kecuali apabila ada alasan medis seperti untuk 6 K.H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, pp. 318-330. 7 menyelamatkan nyawa si ibu. Fatwa itu selanjutnya mengatakan bahwa melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh al-ruh, adalah juga haram, terkecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Fatwa itu juga mengharamkan semua pihak yang terlibat untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.7 Fatwa aborsi kedua ini mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai proses dan tahapan-tahapan penciptaan manusia yaitu Surat AlMukminun ayat 12-14, Surat Al-Hajj ayat 5, dan Surat Al-Isra ayat 33). Fatwa itu juga mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menerangkan tentang waktu peniupan ruh (nafkh alruh) bagi si janin. Kemudian fatwa itu mengutip pendapat ulama yang bermacammacam mengenai hukum aborsi sebelum nafkh al-ruh, ada yang membolehkannya secara mutlak, ada yang membolehkannya karena ada alasan medis (uzur) , ada yang mengatakan makruh, dan ada pula yang mengatakan haram secara mutlak. Fatwa itu pun mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa jika sperma (nuthfah) telah bercampur (ikhtilat) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (ist’idad li qabul al-hayah), maka merusaknya adalah haram hukumnya dan merupakan tindakan pidana. Akhirnya fatwa itu mengutip dua kaidah fiqhiyah, kesatu yang mengatakan: “Menghindarkan kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan,” dan kedua yang mengatakan: “Keadaan darurat membolehkan halhal yang dilarang.” Adapun fatwa aborsi yang ketiga dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2005, dengan alasan karena di dalam masyarakat ketika itu semakin banyak orang melakukan aborsi tanpa mengikuti tuntutan agama dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi sehingga dapat membahayakan ibu yang mengandungnya dan masyarakat secara umum. Fatwa itu mengatakan bahwa aborsi haram hukumnya semenjak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi hanya dibolehkan karena uzur, baik uzur yang bersifat darurat ataupun uzur hajat. Uzur yang bersifat darurat yaitu apabila perempuan yang hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang ditetapkan oleh Tim dokter, atau kehamilan itu mengancam 7 K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, PP. 395-399. 8 nyawa si ibu. Adapun uzur hajat yaitu apabila janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, atau kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya antara lain terdapat keluarga korban, dokter, dan ulama. Fatwa itu menegaskan kebolehan semua aborsi yang dikecualikan itu hanya untuk dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Fatwa itu juga menegaskan bahwa aborsi haram hukumnya bagi kehamilan yang terjadi akibat perbuatan zina.8 Fatwa aborsi ketiga ini mengutip beberapa ayat Al-Quran tentang larangan membunuh anak karena takut kemiskinan (QS Al-An’am ayat 151 dan Isra’ayat 13) dan ayat-ayat Al-Quran mengenai tahapan penciptaan manusia (QS Al-Hajj ayat 5 dan Al-Mukminun ayat 12-14). Fatwa itu juga mengutipkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang proses penciptaan manusia dalam perut ibunya dan saat ditiupkan ruh kepada janin. Dikutipkan juga hadis mengenai diat janin atas pembunuhan wanita yang sedang hamil. Setelah itu dikutipkan empat buah kaidah fiqhiyah yang masing-masingnya mengatakan: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”; ”Menghindarkan kerusakan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan;” “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang;” dan “Hajat terkadang menduduki keadaan darurat.” Pada bagian akhir uraian mengenai landasan fatwa kemudian dikutipkan bahwa ulama sepakat haram hukumnya bila aborsi dilakukan setelah nafkh al-ruh, tetapi ulama berbeda pendapat apabila aborsi dilakukan sebelum nafkh al-ruh. Dikutipkan pula pendapat Syaikh Atiyyah Shaqr, Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar, yang mengatakan bahwa kehamilan karena zina tidak boleh digugurkan kandungannya, tetapi kehamilan karena diperkosa boleh digugurkan kandungannya. Sungguh sangat menarik untuk memperhatikan fatwa MUI mengenai aborsi itu. Pertama, fatwa itu dikeluarkan berulang-ulang karena katanya semakin banyak orang melakukan aborsi tanpa mengikuti aturan agama Islam. Kedua, dari segi dalil yang dikemukakan selalu mengulang dalil-dalil dalam fatwa lama seraya menambahkan dalil-dalil baru baik berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama, maupun kaedah-kaedah hukum yang digunakan. Fatwa kedua lebih lengkap dan lebih kuat dalilnya daripada fatwa pertama dan fatwa ketiga lebih lengkap dan 8 K. H. Makruf Amin, et al, HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975, PP. 455-463. 9 lebih kuat dalilnya daripada fatwa kedua. Ketiga, dari segi aborsi yang boleh dilakukan selalu terjadi perluasan dan penambahan. Aborsi sesudah nafkh al-ruh semua ulama sepakat mengharamkannya, kecuali apabila kehamilan itu membahayakan nyawa si ibu. Hal itu dikatakan oleh fatwa pertama, kedua dan ketiga. Adapun aborsi yang dikecualikan sebelum nafkh al-ruh, diperluas oleh fatwa kedua dengan menambahkan adanya alasan medis lain atau alasan Syariat, selain untuk menyelamatkan nyawa si ibu, meskipun tidak dijelaskan contohnya. Dalam fatwa ketiga, aborsi yang dikecualikan sebelum nafkh al-ruh itu lebih diperketat definisinya, tetapi diperluas lagi cakupannya dengan memasukkan konsep uzur darurat dan uzur hajat. Dikatakan bahwa aborsi itu haram sebelum nafkh al-ruh, maksudnya ialah haram semenjak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Adapun pengecualiannya atas dasar uzur darurat ialah apabila kehamilan itu mengancam nyawa si ibu atau si ibu menderita sakit fisik berat dalam stadium lanjut. Kemudian pengecualiannya atas dasar uzur hajat ialah apabila tim dokter mendeteksi adanya cacat genetika pada si janin atau kehamilan itu terjadi akibat perkosaan yang menimbulkan trauma berat bagi si ibu. Dengan kata lain, fatwa ketiga itu semakin merinci dan menambahi bentuk-bentuk aborsi pengecualian itu. Pertanyaannya ialah apakah pengeluaran fatwa yang berulang-ulang itu berarti telah semakin melonggarkan larangan aborsi ataukah sekedar menambahkan kejelasan (rincian dan precision) dari maksud fatwa-fatwa sebelumnya? Mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.9 ADOPSI FATWA-FATWA MUI DALAM PERATURAN-PERUNDANGAN INDONESIA Terdapat beberapa studi yang menyimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI mempunyai pengaruh kuat dalam proses legislasi di Indonesia. Pertama-tama, Mudzhar dalam penelitiannya mengenai fatwa MUI periode 1975-1989 menemukan bahwa fatwafatwa MUI mengenai soal-soal kedokteran perumusannya dinilai netral, dilakukan secara independen, tidak dipengaruhi oleh politik pemerintah, melainkan semata9 Sebelum fatwa ketiga ini dikeluarkan oleh MUI, sebuah studi yang komprehensif mengenai aborsi ditinjau dari hukum Islam telah dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Jurnalis Uddin, seorang gurubesar pada Universitas Yarsi, Jakarta. Lihat Jurnalis Uddin, et al, REINTERPRETASI HUKUM ISLAM TENTANG ABORSI, penerbit Universitas Yarsi, 2006. 10 mata karena keinginan untuk meresponi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.10 Selanjutnya, Barlinti dalam penelitiannya mengenai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menemukan bahwa fatwa MUI dalam bidang ekonomi Syariah mempunyai kedudukan khusus dan telah diadopsi ke dalam UU Perbankan Syariah Nomor 9 Tahun 2008 dan ke dalam sejumlah regulasi pemerintah mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan pembiayaan.11 Sebelumnya, Adam juga telah menyimpulkan hal yang sama bahwa fatwa-fatwa MUI telah diserap ke dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia, seperti ke dalam UU Sisitim Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dan peraturan perundangan lainnya.12 Pertanyaannya sekarang ialah, apakah fatwa-fatwa MUI tentang bioetika juga telah diserap oleh peraturan perundangan Indonesia? Sebagai landasan pengaturan, dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Pasal 31 ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan manusia. Kemudian dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pasal 22 dinyatakan bahwa pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain daripada itu, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 13 juga telah mengantisipasi produk pangan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika. Pada tataran pelaksanaan, telah dikeluarkan sebuah Surat Keputusan Bersama antara tiga menteri yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian untuk membentuk dan mendirikan Komisi Bioetika Nasional. 10 Mohamad Atho Mudzhar, FATWA-FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA ..., PP. 142-143. Yeni Salma Barlinti, KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA, penerbit Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010, p. 556. Lihat juga H.M. Atho Mudzhar, “K.H. Ma’ruf Amin: Seorang Ulama Yang Cemerlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia,” Pidato Promotor I, disampaikan pada Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada K.H. Ma’ruf Amin Dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 Mei 2012 di Jakarta. 12 Wahiduddin Adam, “Fatwa-fatwa Hukum Majlis Ulama Indonesia (MUI): Pola Terserapnya Dalam Peraturan Perundangan 1975-1997,” disertasi doctor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002. 11 11 Sejauh ini terdapat dua UU kesehatan yang mengatur masalah-masalah terkait bioetika, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terkait transplantasi, dalam UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan disebutkan pada Pasal 33 bahwa dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, tranfusi darah, implant obat, dan atau alat kesehatan bedah plastic dan rekonstruksi. Pada pasal itu juga ditegaskan bahwa transplantasi organ dan jaringan tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Kemudian pada Pasal 34 UU itu diatur bahwa transplantasi organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, serta dilakukan di sarana kesehatan tertentu dan dengan persetujuan donor atau ahli warisnya. Mengenai aborsi, UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada Pasal 15 mengatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu itu dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, dilakukan pada sarana kesehatan tertentu, dan dengan perstujuan ibu hamil yang bersangkutan. Dalam UU Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 terdapat beberapa pasal yang mengatur masalah-masalah bioetika yang telah dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU itu mengatur mengenai transplantasi. Pasal-pasal itu mengatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh itu dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun juga. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan tertentu. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus (wajib) memperhatikan kesehatan 12 pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris keluarganya. Demikianlah pokok-pokok isi kedua pasal itu. Jelas sekali di situ diatur bahwa untuk pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh itu harus mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris keluarganya sebagaimana juga dinyatakan oleh fatwa MUI mengenai hukum transplantasi tersebut di atas. Perbedaan antara fatwa MUI dan UU itu ialah bahwa MUI hanya mengasumsikan si pendonor itu telah wafat, sedangkan UU itu nampaknya memungkinkan si pendonor itu masih hidup seperti tersirat dari kata-kata “harus memperhatikan kesehatan pendonor.” Adapun mengenai aborsi pertama-tama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 hingga Pasal 350. Pada Pasal 346 dikatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada pasal-pasal berikutnya diatur bahwa orang yang membantu seorang wanita melakukan pengguguran atau mematikan kandungannya dengan izin si wanita itu juga adalah tindakan pidana dan diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan apabila tanpa izin si wanita itu maka ancaman hukumannya lebih berat yaitu paling lama duabelas tahun penjara. Pasal-pasal itu berlaku umum dan tidak menyebutkan sesuatu pengecualian, baik untuk menyelamatakan nyawa si ibu ataupun pertimbangan medis umpamanya. Kemudian dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aborsi diatur lagi yang isinya bahwa selain tetap melarang aborsi, tetapi juga memperkenalkan konsep pengecualian, sebagaimana termuat pada Pasal 75 dan 76. Pada Pasal 75 UU itu dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan itu dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi yang dikecualikan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konseler yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan itu akan diatur lebih 13 lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada Pasal 76 diberikan catatan bahwa aborsi-aborsi yang dikecualikan itu hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Juga dipersyaratkan bahwa aborsi yang dikecualikan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang sah, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suaminya kecuali dalam hal korban perkosaan, dan di tempat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Kalau kita perhatikan persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI terakhir tentang aborsi tahun 2005 dan bunyi Pasal 75 dan 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut ternyata hampir seluruh persyaratan bagi aborsi yang dikecualikan itu sama dengan apa yang telah difatwakan oleh MUI, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi Pasal 75 dan 76 itu memang dipengaruhi oleh fatwa MUI yang terbit lebih dahulu dari UU tersebut. Perbedaannya terdapat pada pengaturan dua hal, yaitu bahwa MUI meminta kebolehan aborsi yang dikecualikan itu dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 (empat puluh) hari (sesuai hadis Nabi), sedangkan UU itu mengaturnya dengan istilah “sebelum usia kehamilan enam minggu” yang berarti 42 (empat puluh dua) hari karena penggunaan bilangan minggu memang adalah kelaziman dalam penghitungan usia kehamilan dalam dunia kedokteran. Perbedaan lainnya ialah dalam pengaturan tim konseling, fatwa MUI secara jelas meminta agar dalam hal korban perkosaan tim konseling itu terdiri atas keluarga korban, dokter, dan ulama, sedangkan Pasal 76 UU itu hanya menyebutkan kata “tim konseling” tanpa menyebutkan unsur-unsurnya meskipun masih dijanjikan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang harus kita kaji lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa tidak semua masalah bioetika diatur dalam peraturan perundangan, melalui parlemen atau peraturan oleh pemerintah. Sebagian masalah itu juga diserahkan pengaturannya kepada organisasi-organisasi profesi dan dituangkan dalam bentuk kode etik (Code of Conduct) dan standard profesi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dikatakan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan Kode Etik dan Standard Profesi yang perumusannya dibuat oleh organisasi profesi, seperti Kode Etik Dokter yang disusun dan disahklan oleh organisasi perhimpunan dokter Indonesia bernama Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Demikian pula Kode Etik bagi 14 tenaga kesehatan lainnya, seperti bidan dan perawat. Kode Etik dan Standard Profesi adalah seperti halnya hukum adat (customary law) yang memiliki sifat mengatur, menuntut ketaatan, dan memberikan sanksi, hanya saja sanksinya berbeda dengan sanksi hukum positif. Ketaatan kepada Kode Etik dan Standard Profesi bersumber dari dalam hati, karena nilai dan norma yang dianut. Apabila terjadi pelanggaran, maka penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Standard Profesi biasanya dilakukan dengan mediasi yang tidak menuntut pembuktian, sedangkan pemberian sanksinya bersifat social seperti dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi dan sebagainya. Adapun peraturan perundangan, sifatnya mengatur dan memaksa, serta sanksinya dapat berupa kurungan badan atau denda. Meskipun demikian, sebuah pelanggaran yang pada awalnya dipersepsikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Standard Profesi, dapat juga berujung menjadi pelanggaran peraturan perundangan atau tindakan pidana apabila terdapat buktibukti yang mendukungnya. CATATAN PENUTUP Demikianlah beberapa catatan tentang dua fatwa MUI yang terkait masalah bioetika, yaitu mengenai transplantasi dan aborsi. Dari uraian di atas nampaklah bahwa MUI telah memberikan respon terhadap sejumlah masalah bioetika sebagai upayanya untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan memberikan bimbingan kepada umat Islam. Sebagian fatwa bioetika MUI itu ternyata telah direspon oleh masyarakat dan pemerintah dan diadopsi dengan berbagai modifikasi dalam legislasi di Indonesia. Tentulah MUI masih perlu terus mengeluarkan fatwa-fatwa berikutnya di bidang bioetika pada masa yang akan datang. Kedepan analisis seperti inipun perlu diteruskan, karena uraian ini barulah membahas dua fatwa dari delapan fatwa MUI yang sudah terbit mengenai hal ini. Insya Allah. *** 15