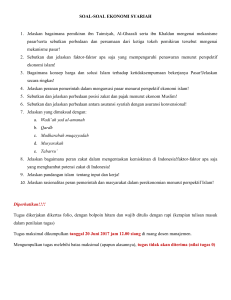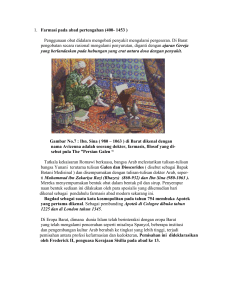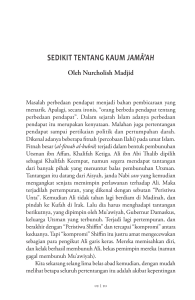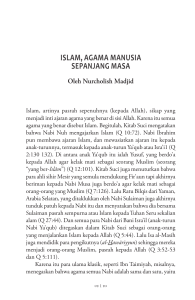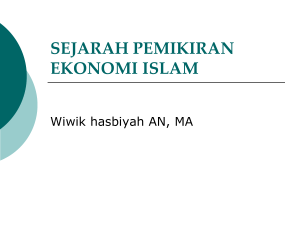skeptisisme teologis dan jawaban filsafat
advertisement

68 SKEPTISISME TEOLOGIS DAN JAWABAN FILSAFAT Norbertus Jegalus Abstract Human language deals with sense experience. When human language has to speak on God, there comes the problem on which experience man can talk about Him. For God does not deal with human sense experience. How is it possible to use human language which is limited to his sense experience, to speak on God without lowering Him on human level? It precisely is the possibility of analogy. Analogy makes human language remain limited to his dimensional life and, at the same time, gives the possibility to speak on and talk with God. For essentially human being is spiritual and his language by his reason and the will contains human capacity to reach God. Keywords Reason. Analogy. Will. Logos. Transendence. Transconceptional. Abstrak Bahasa manusia adalah bahasa yang berhubungan dengan pengalaman indrawi. Namun bahasa itu justru dipakai oleh manusia untuk berbicara tentang Allah padahal Allah itu bukanlah realitas indrawi. Bagaimana mungkin bahasa insani yang bersifat indrawi itu mungkin berbicara tentang Allah. Jawabannya, manusia mungkin berbicara tentang Allah, dengan tanpa merendahkan Allah menjadi setaraf dengan manusia, dan itulah kemungkinan bahasa analog tentang Allah. Dengan analogi itu, manusia, meski secara terbatas, mampu mengenal dan berbicara tentang Allah, karena ia bukanlah materi belaka melainkan makhluk rohani. Kerohanian itulah yang memungkinkan manusia, melalui dinamisme akal dan kehendak, mampu berbahasa dan mencapai Allah dalam bahasa insani yang sensibilis. Kata-kata kunci: akal budi, analogi, kehendak, logos, transendensi, transkonsepsional. 69 1. Pendahuluan Skeptisisme teologis dalam teologi kontemporer umumnya berdasarkan pada tiga hal yakni kodrat pengetahuan manusia, kodrat Allah itu sendiri dan kodrat bahasa manusia. Di sini kita lebih meninjau skeptisisme teologis berdasarkan kodrat bahasa manusia, kemudian berusaha menemukan jawabannya dari dunia filsafat, khususnya dari filsafat Skolastik, yang dari segi inti teorinya masih relevan untuk menanggapi skeptisisme teologis kontemporer itu, yaitu teori analogi.1 Persoalan kaum skepsis teologis di sini adalah bahwa bahasa manusia tidak mampu berfungsi sebagai pembawa informasi tentang Allah, karena bahasa manusia itu selalu bereferensi kepada hal-hal material sementara Allah yang mau dibahasakan justru sama sekali tidak berkaitan dengan dunia material. Skeptisisme teologis berargumentasi bahwa bahasa manusia sama seperti pengetahuan manusia, muncul dari pengalaman indrawi; bahasa bertumbuh dari peniruan anak-anak terhadap penggunaan bahasa orangtua mereka. Jadi kata-kata mempunyai asal-usulnya dari pengalaman indrawi; rujukan orisinal bagi setiap kata adalah sesuatu yang bersifat fisis. Nah, bagaimana kata-kata yang mempunyai rujukan orisinal yang bersifat fisis tiba-tiba bisa merujuk secara memadai kepada sesuatu yang spiritual dan nonspasial, yaitu Allah?2 Karl Barth adalah salah satu teolog kontemporer yang memandang bahasa manusia sebagai instrumen yang tidak memadai untuk menyampaikan kebenaran Allah. Di dalam opus magnum teologinya, Church Dogmatics, ia menulis: Gambaran-gambaran yang di dalamnya kita memandang Allah, 1 Bdk. Leslie Dewart, The Future of Belief. Theism in a World Come of Age, London: Burn & Oates, 1967, hlm. 179:“The doctrine of analogy is the logical outcome of attempting to explain how we can conceive God while holding simultaneously (a) that knowledge is an intentional intussusception through the means of concepts, (b) that all our concepts are derived from empirical intuition, and (c) that God is not, at least “here below”, known to us by any empirical intuition. The solution consists in supposing that concepts derived from empirical intuition can adequately reach an object beyond empirical intuition if only we recognize, avow and state that such concepts cannot adequately reach an object beyond empirical intuition”. 2 Bdk. Jan Aler, “Heidegger’s Conception of Language in Being and Time”, dalam, Joseph J. Kockelmans, On Heidegger and Language, Evanston: Northwestern University Press, 1986, hlm. 50-51; juga, Joseph J. Kockelmans, “Language, Meaning, and Ek-sistence”, dalam, ibid., hlm. 22-23. 70 pemikiran-pemikiran yang di dalamnya kita memikirkan-Nya, kata-kata yang dengannya kita mendefinisikan-Nya, sebenarnya semua itu tidak layak bagi objek ini dan oleh karena itu tidak tepat untuk mengekspresikan dan menegaskan pengetahuan mengenai Dia”. 3 Masalah yang dihadapi Karl Barth di sini kita dapat rumuskan secara filosofis demikian: Bahasa yang kita pakai setiap hari adalah bahasa yang berasal dari pengalaman insani kita. Namun, bila kita berbicara tentang Allah justru kita menggunakan bahasa yang sama, padahal Allah itu adalah suatu realitas yang melampui pengalaman insani kita. Allah adalah realitas adi-alami yang mengatasi segala-galanya secara tak terbatas, sedang bahasa insani kita bagaimanapun sempurnanya tetap bersifat terbatas, karena bahasa itu mempunyai ketergantungan ekstrinsik kepada materi. Jadi, di satu pihak ada keterbatasan, yaitu bahasa insani selalu bereferensi kepada pengalaman indrawi, sementara di lain pihak ada ketakterbatasan, yaitu kesempurnaan mutlak dari objek yang mau dibahasakan. Pertanyaan pun muncul, masihkah kita ketahui, kita berbicara tentang apa, bila bahasa insani kita pakai untuk menunjukkan Allah? Apakah bahasa yang kita pakai untuk menunjukkan Allah itu, bisa diambil begitu saja dari bahasa yang kita gunakan dalam konteks pengalaman konkret kita? Apakah bahasa yang selalu berkaitan dengan dunia terbatas itu, bisa diterapkan begitu saja kepada Allah yang tak terbatas? Bukankah Allah itu unik, berlainan sama sekali dengan segala sesuatu yang lain? Di sini masalahnya adalah inaedequatio (ketidaksesuaian) antara sarana bahasa dan objek yang dibahasakan. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang terdiri dari konsep-konsep, dan konsep itu tidak lain adalah representasi, yaitu suatu gambaran akali atas realitas material. Ketergantungan ekstrinsik pada materi inilah yang membuat pengetahuan manusia itu pada hakekatnya terikat pada dunia sensibilis, sehingga selamanya dan bagaimana pun sempurnanya, tetap tidak mungkin mengungkapkan secara memadai realitas ilahi.4 3 Karl Barth, Churh Dogmatics, Vol. II: The Doctrine of God, ed. G.W.Bromiley & T.F. Torrance, New York: Scribner, 1957, hlm. 188. 4 Bdk. F. Verre, “Analogy in Theology”, dalam, P. Edwards (ed), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. I, New York-London, 1967, hlm. 94-97. 71 2. Bahasa Manusia Dan Realitas Ilahi Jawaban Filsafat atas Skeptisisme Teologis itu adalah bahwa bagaimanapun kita harus menggunakan konsep-konsep insani kalau kita berbicara tentang Allah, sebab tanpa konsep itu mustahil kita berpikir dan berbahasa. Tidak ada jalan lain selain kalau kita berbicara tentang Allah maka di situ kita harus memperbaiki konsep-konsep insani itu dengan meniadakan sifat-sifat terbatas yang dimilikinya. Bagaimanakah itu mungkin dilakukan? St. Thomas Aquinas dengan teori analogi mengatakan bahwa Allah itu untuk sebagian adalah tidak beda dari ada-ada yang ditunjuk oleh konsep-konsep insani yang bersifat sensibilis itu dan untuk sebagian bukan seperti ada-ada it.5 Itulah cara membahasakan Allah secara analog, dan cara itulah yang memadai tentang Allah. Sedangkan membahasakan Allah secara univok dan ekuivok ditolak, karena bahasa univok membawa kita kepada bahaya antropomorfisme dan bahasa ekuivok membawa kita kepada bahaya agnostisisme. 2. 1. Membahasakan Allah Secara Univok Bahasa kita mengenai Allah jelas tidak bisa secara univok.6 Kita tidak bisa memakai suatu term dalam arti yang satu dan sama mengenai Allah yang in ordine essendi adalah tak terbatas dan mengenai manusia in ordine essendi adalah terbatas. Seturut status ontologis ini maka jelas bahwa kata-kata yang kita pakai untuk menunjukkan manusia atau ciptaan sebagai realitas terbatas, tidak bisa dipakai dalam arti yang satu dan sama mengenai Allah sebagai realitas tak terbatas. Karena itu, kata-kata yang kita pakai untuk ciptaan, manakala kata-kata itu kita kenakan kepada Allah, artinya tentu 5 Teks-teks terpenting Thomas Aquinas tentang masalah analogi terdapat dalam, Summa Thelogia I, q. 13, a.5 dan 6; dan juga dalam, Summa contra Gentiles I, 34. 6 Suatu term disebut univok berarti term itu dipakai dua kali atau lebih untuk barang apa saja dengan arti yang sama. Dengan kata lain, satu kata dipakai mengenai beberapa barang dalam arti yang persis sama. Demikian misalnya, “Petrus manusia” dan “Maria manusia”. Term “manusia” di sini adalah term univok, yang memberikan informasi yang persis sama mengenai Petrus dan Maria. Kandungan makna kata “manusia” dari kedua kalimat itu tidak berbeda. Kemanusiaan pada Maria sama persis dengan kemanusiaan pada Petrus. 72 tidak sama. Kata bijaksana dikenakan kepada Allah, seperti Allah bijaksana”, tentu artinya tidak sama persis manakala kata yang sama kita kenakan kepada manusia seperti “kepala sekolah bijaksana”. Maka dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa distinksi berikut: (1) Bijaksananya kepala sekolah itu hanya dalam hal tertentu, mungkin dalam hal ini, hanya mengenai pendidikan dan soal-soal berhubungan dengan kurikulum sekolah, namun ia tidak bijaksana mengenai segala hal. (2) Bijaksananya kepala sekolah itu sampai sekarang, namun tidak pasti bahwa ia selamanya bijaksana. (3) Ia belajar banyak untuk menjadi bijaksana, entah melalui pengalaman atau studi akademis, dan tidak begitu saja, ia menjadi bijaksana. Singkatnya, tidak dari sendirinya, tidak selalu dan tidak selamanya dan tidak mengenai segalanya, ia bijaksana. Bagaimanapun luar biasa bijaksananya kepala sekolah itu, tetap bijaksananya bersifat terbatas. Tentu saja semua konotasi yang memperlihatkan keterbatasan itu tidak bisa kita kenakan begitu saja kepada Allah, walaupun kita bisa mengatakan bahwa Allah bijaksana. Kalau kita berbicara mengenai Allah, maka kita harus perhatikan bahwa dalam hal itu, maksud kita tidak persis sama dengan apa yang kita maksudkan dengan cara berbicara itu mengenai manusia atau ciptaan pada umumnya. Manakala kita berbicara tentang Allah dan manusia secara persis sama, secara univok, maka dengan itu kita menyetarafkan Allah dengan manusia. Padahal secara ontologis kita telah akui bahwa Allah itu sebagai “ada yang tak terbatas” dan manusia sebagai “ada yang terbatas”. Itulah bahaya antropomorfisme dalam pemakain bahasa univok mengenai realitas ilahi. Padahal kalau kita memakai pengertian bijaksana itu, maka dengan sifat itu kita maksudkan sebagai kualitas yang ada pada manusia, yang lalu dikenakan kepada Allah dalam tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian pemakaian bahasa secara univok mengenai Allah akan menghilangkan nilai absolut dari ada yang dimiliki Allah. Padahal Allah adalah ens a se, Ia adalah ada dari sendirinya. Sedangkan barang ciptaan, memang mereka ada namun tidak berada dari sendirinya. Mereka menjadi ada selalu oleh yang lain (ens ab alio), yang dalam hal ini adalah oleh Allah. Allah adalah asal dari segala apa saja yang ada. Sekalipun Allah itu sendiri disebut sebagai ada, namun pengertian ada di sini tidak persis sama dengan pengertian ada pada makhluk ciptaan. Karenanya, ada di sini tidak bisa 73 dipakai secara univok mengenai Tuhan dan makhluk ciptaan. Kalimat seperti “Tuhan ada” dan “Manusia ada,” hanya secara logis sama, sebab pengertian ada di sini berlaku sebagai predikat. Akan tetapi, secara ontologis justru sangat jauh berbeda. Ada bagi manusia adalah “ada yang diadakan”, sedangkan ada bagi Allah adalah “ada yang tidak diadakan”. Bahasa kita harus mengatakan bahwa Allah itu adalah ada, dan ada itu sebenarnya tidak lain adalah Allah. Analisis hubungan sebab-akibat juga bisa memperlihatkan ketidakmungkinan pemakaian bahasa seperti itu mengenai Allah. Prinsip metafisik mengatakan bahwa “kesempurnaan pada sebab sama dengan kesempurnaan pada akibat”. Itulah asas tentang sebab univok. Demikian misalnya, seorang anak adalah termasuk spesies yang sama dengan orangtuanya. Dalam hal ini, orangtua adalah sebab univok bagi lahirnya seorang anak. Dari manusia hanya menurunkan seorang anak manusia dan bukan seekor hewan. Dari seekor kerbau hanya menurukan seekor anak kerbau bukan seekor kuda, sekalipun kuda dan kerbau sama-sama hewan. Kita tidak bisa menantikan munculnya seekor kuda dari sebutir telur ayam, sebab ayam bukan sebab univok bagi kuda. Apakah ada yang dimiliki Tuhan atau salah satu kesempurnaan yang dimilikiNya, di mana kesempurnaan itu identik dengan ada tersebut, bisa menjadi sebab univok dari ada pada makhluk ciptaan? Kalau jawabannya bisa, maka itu berarti Tuhan tidak lagi berlaku sebagai sebab universal bagi kesempurnaan yang makhluk ciptaan miliki. Tegasnya, hubungan antara Allah di satu pihak dan makhluk ciptaan di pihak lain, tidak bisa dipandang dalam konteks sebab univok. Kalau kepada Allah kita kenakan pengertian sebab univok, maka itu berarti makhluk ciptaan sebagai akibatnya memiliki kesempurnaan yang serupa dengan Allah. Bisa saja kita mengatakan bahwa yang memiliki keserupaan dalam kesempurnaan dengan Allah adalah manusia. Jadi manusia adalah akibat univok dari sebabnya Tuhan. Akan tetapi, bagaimankah kita harus menjelaskan bahwa ciptaan di atas alam semesta ini begitu banyak jenisnya, tidak hanya manusia. Apakah ciptaan-ciptaan itu tidak disebabkan oleh Allah? Jawabannya, jelas bahwa semua itu diadakan oleh Allah. Tak ada satu barangpun di atas alam ini yang menjadi ada oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun segalanya dijadikan oleh Allah, kecuali Allah sendiri. 74 Dengan demikian, Allah adalah sebab dari segala sesuatu yang ada, tetapi bukan sebagai sebab univok melainkan sebagai sebab universal. Segalanya adalah Allah sebagai sebab adanya. Di situlah Allah dilihat sebagai sebab universal bagi apa saja yang ada. Oleh karena itu, pengertian sebab univok mengenai Tuhan tidak berlaku. Seandainya pengertian semacam itu dikenakan kepada ciptaanNya, maka dengan itu pula Allah disetarafkan dengan makhluk ciptaanNya (antropomorfisme). 2. 2. Membahasakan Allah Secara Ekuivok Karena membahasakan Allah itu secara univok tidak mungkin, lantas kita berpikir, kalau begitu kita membahasakanNya secara ekuivok7 untuk menunjukkan bahwa Allah itu di mata manusia tidak sekadar lain tetapi benar-benar lain. Manusia memandang Allah tidak sekedar lain dari dirinya tetapi bahwa Allah itu sebagai yang sama sekali lain. Maka bahasa kita tentang Dia haruslah dalam arti sama sekali lain dari pemakaiannya tentang makhluk ciptaan.8 Terhadap pendapat seperti ini kita patut mengajukan pertanyaan: Manakala kita berkata bahwa Allah itu bijaksana, apakah kata bijaksana itu mempunyai arti sama sekali lain tatkala kita memakai kata yang sama tentang manusia? Kalau kita berkata, “Allah itu bijaksana”, apakah kita seakan mendengar suatu bahasa yang tidak kita kuasai? Tentu Tidak. Kata bijaksana itu adalah kata yang biasa kita pakai mengenai manusia, dan tatkala kata itu dipakai mengenai Allah sebagai yang lain dari manusia, maka kita tetap mengerti maksudnya. Justru kita mengerti pemakaiannya mengenai Allah 7 Suatu term adalah ekuivok, kalau term yang dimaksud dikenakan kepada dua hal atau lebih hal, yang sama sekali lain, dalam arti yang berlainan pula. Term ekuivok itu memiliki dua atau lebih arti yang benar-benar berbeda. Kata “membajak” dalam kalimat “Petrus membajak sawah” dan “Petrus membajak pesawat terbang”, berlainan sama sekali artinya. 8 Pandangan ini membawa kita kepada agnostisisme teologis yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan; manusia tidak bisa mengenal Allah yang transenden. Tiga teolog kontemporer menganut angnostisisme teologis ini, seperti: Gordon D. Kaufmann, dengan karyanya, God the Problem (Cambridge: Harvard University Press, 1972); John Baillie, dengan karyanya, The Ideas of Reveraltion in Recent Thought (New York: Columbia University Press, 1956), dan William Temple, dengan karyanya, Nature, Man and God (New York: St. Martin’s Press, 1934). 75 setelah kita mengerti bagaimana kata itu dipakai tentang manusia. Kalau kita tidak memahami artinya dikenakan kepada manusia, maka mustahil pula kita mengerti artinya bila dikenakan kepada Allah. Kalau berbicara tentang manusia dan Allah secara ekuivok, maka itu berarti, bagi kita manusia, kata Allah itu sendiri dan apa saja yang dikatakan tentangNya tidak akan mempunyai makna apa pun. Karena itu, kata baik, misalnya, tidak bisa dipakai tentang manusia dan Tuhan secara ekuivok, di mana artinya benar-benar berlainan untuk keduanya. Bagaimanapun antara Tuhan dan manusia ada hubungan. Tuhan adalah sebab dari adanya manusia. Itu berarti, ada relasi kemiripan antara sebab di satu pihak yakni Allah dan akibat di pihak lain yakni manusia. Seandainya atribut baik atau atribut-atribut lainnya dipakai secara ekuivok, maka bagi kita manusia menjadi mustahil untuk membuktikan adanya Tuhan dan selanjutnya menjadi mustahil pula untuk menyimpulkan bagaimana pengertian atau kesempurnaan baik itu terdapat pada manusia. Sebenarnya kalau kita mengatakan “Tuhan baik”, maka kita tentu bermaksud lebih dari pada mengatakan “Tuhan tidak jahat” (via negationis), atau “Tuhan baik”, itu berarti, menegaskan bahwa yang dinamakan kebaikan pada makhluk itu sebenarnya terdapat pada Tuhan secara lebih dahulu atau secara lebih tinggi dan secara seharusnya (per naturam), sedangkan kesempurnaan yang sama ada pada manusia secara tidak seharusnya (per accidens). 2. 3. Membahasakan Allah Secara Analog Suatu pengertian bersifat analog, kalau sebagian artinya sama dan sebagian artinya berlainan. Dengan kata lain, suatu kata dipakai tentang banyak barang dalam arti yang sama sekaligus beda. Jadi, pengertian atau kata itu dikenakan kepada banyak barang tidak dalam arti sama sekali sama namun juga tidak sama sekali beda, tetapi sekaligus sama dan beda. Secara empirik kita dapat membagi analogi dalam dua kategori, yakni analogi pada tataran supra-human yakni menyangkut pengenaan suatu kata kepada manusia dan kepada yang melampaui manusia, dan analogi pada tataran infra-human yakni menyangkut pengenaan suatu kata kepada manusia dan kepada makhluk yang secara ontologis berada di bawah manusia 76 yaitu binatang. Macam analogi yang pertama dapat kita namakan analogi ke arah atas, dan macam analogi kedua kita sebut analogi kea rah bawah. Seekor anjing disebut setia. Dengan mengatakan seekor anjing setia, itu berarti beberapa ciri yang terdapat pada manusia yang setia terdapat pula pada anjing. Akan tetapi, sekalipun anjing itu desebut setia sebagaimana seorang manusia disebut setia, namun kesetiaan pada taraf manusia jelas berbeda sekali dengan kesetiaan pada taraf binatang. Pada tarap anjing terdapat kualitas yang sesuai dengan apa yang disebut setia pada taraf insani. Kita mengerti, seekor anjing itu setia, sejauh kita mengerti bagaimana kualitas yang sama dipakai mengenai manusia. Yang sesungguhnya memiliki kualitas setia hanya manusia. Karena itu kita baru mengerti bagaimana kesetiaan pada binatang anjing itu setelah kita mengerti mengenai kesetiaan pada manusia. Sedangkan analogi ke arah atas, manakala kata atau pengertian yang dipakai mengenai manusia dipakai juga mengenai Allah yang melampaui manusia pada taraf apapun. Pengertian kebaikan dan kebijaksanaan bisa dikenakan kepada Allah. Maka itu berarti kedua kualitas itu sejauh mengenai Allah adalah sempurna. Maksudnya, kedua kualitas itu dipakai mengenai Allah dalam arti yang sempurna, dan dipakai mengenai manusia hanya secara analog. Karena itu, kita tidak menempatkan kata-kata itu secara persis sama seperti mengenai manusia. Juga tidak berarti bahwa kata-kata itu kalau dipakai mengenai Allah maka artinya menjadi lain sama sekali (ekuivok). Akan tetapi, kata-kata itu dipakai mengenai Allah justru setelah kita mengerti bagaimana pemakaiannya pada taraf insani yakni dalam pengalaman insani kita. Kita mengerti maksud kata-kata itu tentang Allah setelah kita pertamatama tahu apa yang dimaksudkan manusia dalam pengalaman sehari-hari dengan kebaikan dan kebijaksanaan. 3. Analogi Dan Transendensi 3.1. Dasar adalah Analogia Entis9 Mengenai ada kita harus mengatakan bahwa ada dari apa saja memang tidak sama satu sama lain namun bagaimanapun tetap mempunyai kesamaan dengan yang lain. Dengan kata lain, dalam keanekaan dan kejamakan yang tidak terbatas dari apa saja yang ada, terdapat suatu kesamaan dan perbedaan. 9 Norbertus Jegalus, ” Metafisika Dasar ” (Materi Kuliah Tatap Muka pada Fakultas Filsafat Agama, Universitas Widya Mandira), Kupang, 2009, hlm. 33-37. 77 Menjadi sama dengan semua apa saja karena semua sebenarnya adalah berada dan menjadi beda karena semua itu selalu “berada sebagai ini atau sebagai itu”, sehingga tidak ada dua barang yang benar-benar sama. Konsep ada itu mengungkapkan masing-masing substansi pada segala taraf menurut seluruh realitasnya dan menurut segala aspeknya. Apa saja yang ada, ditangkap dengan konsep ada ini, dan apa saja yang tak terungkapkan di dalamnya, memang itu tidak ada. Substansi-substansi tidak memiliki ada mereka secara terpisah-pisah, berdampingan saja, atau dengan dibandingkan satu sama lain dari jauh, melainkan mereka memiliki ada itu dalam komunikasi dan kebersamaan. Maka, dengan konsep ada ini semua substansi ditangkap menurut kesamaan mereka timbal-balik dalam hal berada. Itu berlaku bagi tanah, hewan, pohon, manusia dan Tuhan. Jadi, konsep ada berarti universal dan sama bagi segala substansi. Dari lain pihak karena tidak apa-apa dikecualikan dari konsep ada, maka konsep ada itu diucapkan mengenai apa saja justru menurut kemandirian dan perbedaanya. Konsep ada itu mancakup semua substansi mana saja menurut kesendiriannya yang konkret, entah itu mengenai Tuhan, orang ini, kuda itu, bunga yang indah di sana, atau batu keras itu, pokoknya pengenaan ada kepada semua itu dengan segala unsur individualitasnya. Oleh karena itu, konsep ada mengungkapkan juga sifat konkret-individualunik dari masing-masing barang. Akan tetapi, kalau di sini dikatakan bahwa mengenai ada ini ada kesamaan, namun kesamaan antara segala yang ada bukanlah kesamaan yang sederhana dan langsung antara dua barang, melainkan kesamaan yang sebanding (proporsional). Kesamaan antara barang yang satu dengan barang yang lain didasarkan bukan atas bagian-bagiannya, melainkan “kesamaan hubungan” antara bagian-bagian itu. Ada kesamaan antara barang-barang, karena pada barang yang satu dan barang yang lain ada proporsi bagianbagian, yaitu proporsi hubungan antara bagian essentia dan bagian actus essendi. Ada kesamaan dalam ada antara dua barang apa saja yang berbeda, karena masing-masing mereka menjalankan actus essendi sepadan (proporsi) dengan essensinya. Misalnya, sepotong besi berada sepadan dengan essensi 78 kebesiannya. Tumbuh-tumbuhan berada sepadan atau proporsional dengan essensi ketumbuhannya. Walaupun tidak ada dua barang yang mempunyai actus essendi (aktus berada) yang sama, namun segala barang yang berbeda mempunyai actus essendi itu secara sepadan dengan essensinya. Karena itu, betapapun besarnya perbedaan antara dua barang apa saja, namun mereka selalu mirip mengenai hubungan actus essendi dan essentia mereka. Garam berada sesuai dengan essensi kegaramannya, persis sama seperti bunga berada sesuai dengan essensi kebungaannya. Adapun analogia entis didasarkan atas kesamaan hubungan actus essendi dan essentia seperti itu. 3.2. Penggunaan Analogia Transcendentalis Berdasarkan analogia entis itu kita dapat berbicara tentang analogia transcendentalis, yaitu suatu analogi yang berkaitan dengan realitas transenden. Dalam cahaya analogia entis itu kita dapat berbicara tentang realitas ilahi, dan dalam pembicaraan tentang Allah itu, kita tidak menerapkan istilah-istilah analog pada Allah dengan mempersatukan istilah-istilah positif dan negatif yang sebelumnya sudah diakui. Kita hanya mencapai konsepkonsep yang positif dan yang negatif dengan menganalisis konsep-konsep yang mentransendensikan, yang menyatakan dinamika akal kita.10 Kita bisa mengafirmasi beberapa sifat tentang Allah dan juga bisa menegasi sifat-sifat tertentu dimilikiNya, tidak dengan cara sebagaimana sifat-sifat itu terdapat dalam makhluk ciptaan. Mengapa? Karena Allah kita kenal sebagai Dia yang selalu ada di atas apa pun yang dapat kita gambarkan, sebagai objek terakhir dan memuaskan secara sempurna dari dinamisme akal11 serta kehendak manusia. 10 Leslie Dewart, Op. Cit., hlm. 81: “Man can know not only beings, but be-ing; not only being-as-other, but also being itself. He can not only become “the other as other” (aliud in quantum aliud), but also be other as himself. Thus, the basic characteristic of human existence (revealed by the fact that, being conscious, man is the being, as it were, whose being is outside himself) is sometimes called transcendence”. 11 Bdk. Ronadl H. Nash, Firman Allah dan Akal Budi Manusia (Terj. Sulyani Wiryo), Surabaya: Penerbit Momentum, hlm. 175: “Natur Allah maupun natur pengetahuan manusia dan natur bahasa tidak meniadakan kemungkinan bagi akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan kognitif mengenai Firman Allah”. 79 3. 2.1. Allah Dan Analogia Atributionis Dalam analogia atributionis ini, satu dari beberapa analogata memiliki suatu ciri dalam arti yang sebenarnya sedangkan kepada yang lain ciri itu dikenakan (atributed) dalam arti sampingan atau turunan. Hal atau barang yang memiliki kualitas dalam arti yang sebenarnya disebut primum analogatum atau princeps analogatum. Sedangkan hal-hal atau barangbarang yang kepada mereka kualitas itu dikenakan dalam arti turunan disebut secunda analogata. Kata sehat, misalnya, dapat disebutkan tentang tubuh, pakaian, olahraga, makanan, rumah. Sekalipun kata sehat itu bisa dikenakan kepada banyak hal atau memberikan informasi tentang banyak hal, namun informasi yang disebutkan itu tidak sama persis satu dengan yang lain, tetapi juga tidak sama sekali lain satu dengan yang lain. Sehat hanya dipakai dalam arti yang sebenarnya mengenai “tubuh”. Secara sebenarnya kita hanya bisa mengatakan “tubuh sehat”. Dalam hal ini “tubuh” sebagai primum analogatum, sedangkan mengenai hal-hal lain seperti pakaian, olahraga, makanan dan rumah, kata sehat dikenakan kepada mereka melulu berdasarkan perbandingan dengan primum analogatum “tubuh” ini. Perbandingan itu dibuat berdasarkan relasi antara “tubuh” di satu pihak, dan pakaian, olahraga, makanan dan rumah di pihak lain. Bahwa pakain, olahraga, makanan dan rumah, atas suatu keadaan dan cara tertentu, semua itu menjadi sebab bagi adanya kesehatan pada “tubuh”.12 Masalah bahasa teologis terletak dalam hal ini, bahwa bahasa itu justru pertama-tama dalam tataran indrawi dipakai mengenai barang-barang di luar Allah. Kata-kata yang kita pakai untuk menunjukkan dunia pengalaman kita, kita gunakan dalam arti yang sebenarnya dan itu berarti sebagai primum analogatum, kemudian kata yang sama itu kita kenakan kepada Allah menurut suatu relasi dengan arti yang pertama itu. Maka, dalam hal ini, Allah sebagai secundum analogatum. Kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh pengertian itu dikenakan kepada Allah, bilamana pertama atau sebelumnya kita tahu apa maksud kata itu mengenai makhluk ciptaan. Terlebih dahulu ada arti biasa dalam 12 Thomas Aquinas, ST I.q.13.a.5, dan Bdk. Penjelasan Edward Schillebeckx, Revelation and Theology Vol. 2. The Concept of Truth and Theological Renewal, London: Sheed and Ward, 1987, hlm. 199-200. 80 pengalaman insani barulah kemudian kita pakai kata itu dalam arti turunan mengenai “yang maha lain”, namun artinya tidak menjadi sama sekali lain. Kalau artinya menjadi sama sekali lain, yaitu tidak ada hubungan dengan arti yang biasa dalam pemakaian insani sehari-hari, maka kita kembali jatuh ke dalam bahaya agnostisisme. Tetapi juga tidak berarti bahwa kata itu dipakai dalam arti yang persis sama dengan pemakaian insani sehari-hari. Jika seperti itu, maka kita kembali jatuh ke dalam bahaya antropomorfisme. Namun kita perlu memperhatikan cara relasi antara primum analogatum di satu pihak dan secunda analogata di pihak lain. Pada orde epistemologis, yakni pada tataran mengenal insani, yang merupakan primum analogatum adalah kata-kata itu dipakai dalam arti yang sebenarnya mengenai manusia sedang kepada secunda analogata dikenakan dalam arti turunan. Jadi pada tataran mengenal manusiawi yang selalu merupakan kerja sama antara sensus (indra) dan intellectus (akal budi), kata-kata itu dipakai dalam arti yang sebenarnya, dan justru setelah kita mengerti pemakaian kata-kata itu dalam kehidupan sehari-ahri barulah menjadi mungkin untuk kita kenakan kepada yang melampaui pengalaman indrawi. Kalau kita tidak mengerti artinya dalam pemakaian sehari-hari, maka mustahil kita mengerti pengenaannya kepada Allah, sebab pemakaian kepada Allah itu hanyalah dalam arti turunan. Harus ada arti yang pertama sebagai arti yang sebenarnya. Kita bisa kenakan kepada Allah bahwa Allah itu baik, karena adanya suatu relasi dengan kebaikan yang kita alami setiap hari pada taraf pengenalan insani. Kebaikan pada pengalaman insani setiap hari merupakan primum analogatum, sedangkan kualitas itu dikenakan kepada Allah selalu merupakan secundum analogatum. Akan tetapi, kita tidak boleh memahami bahwa pemakaian kata baik kepada Allah hanya sebagai pemakain simbolis. Teori analogi justru mau menjernihkan pemahaman seperti ini. Sedangkan pada orde ontologis justru sebaliknya terjadi. Kata-kata itu dipakai dalam arti yang sebenarnya yaitu sebagai primum analogatum bagi Allah dan dalam arti turunan yaitu sebagai secunda analogata mengenai barang ciptaan. Itulah sebabnya tentang kualitas baik tadi, hauslah kita mengatakan bahwa “Allah baik” dan itu dipakai dalam arti yang sebenarnya. Kalau kita mengatakan bahwa “Tuhan baik”, maka predikat baik di sini kita tidak maksudkan sebagai sesuatu yang lain dari essensiNya sebab “Tuhan adalah kebaikan”. Sedangkan bagi manusia, kata baik itu dikenakan kepadanya 81 namun tidak menyangkut essensinya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa “manusia adalah kebaikan”. Antara kebaikan dan manusia ada distinksi, sedang antara Tuhan dan kebaikan ada identitas. Pada Allah tidak ada distinksi antara pengertian baik dan diriNya. Karena itu, Tuhan disebut sebagai sumber dan sebab dari segala sesuatu yang dikatakan baik pada taraf ciptaan. 3. 2.2. Allah Dan Analogia Proportionalitatis Dalam analogia proportionalitatis ini terdapat kemiripan dua proporsi. Dua hal atau barang (res) memiliki ciri dalam arti yang sebenarnya tetapi hanya sesuai (proportio)13 menurut kodratnya masing-masing. Analogi ini mengungkapkan kemiripan kualitas yang terdapat pada manusia di satu pihak dan kualitas yang dikenakan kepada Allah di pihak lain berdasarkan natura masing-masingnya. Suatu kualitas bisa dipakai mengenai manusia dan Allah, masing-masing dalam arti yang sebenarnya, namun yang proporsional dengan kodratnya masing-masing. Dengan ini Skolastik berhasil mempertahankan perbedaan antara taraf ilahi di satu pihak dan taraf insani di pihak lain, dalam hal membahasakan keduanya. Juga dengan analogi model ini, Skolastik berhasil mempertahankan adanya suatu kesamaan kedua taraf tersebut. Analogi model ini masih dibagi lagi atas analogia proportionalitatis propriae (analogi sepadan) dan analogia proportionalitatis impropriae (analogi tak sepadan). Dalam analogia proportionalitatis proporiae, dua barang ditempatkan dalam realitas yang sama. Realitas itu terdapat di dalam kedua hal tersebut. Pernyataan “Tuhan ada” dan “manusia ada”, di sini eksistensi Allah dan manusia dihubungkan dalam realitas yang sama yang per essentiam berbeda pula. Skolastik menegaskan bahwa secara seharusnya hanya dikenakan pada Allah atribu-atribut yang mengijinkan suatu modus essendi yang tak terbatas. Karena itu analogi sepadan ini lebih berkaitan dengan perfectiones simplices, yaitu mengenai kesempurnaan-kesempurnaan yang dari kodartnya sendiri sedikitpun tidak mengandung ketidaksempurnaan. Itu berarti, analogi ini menyangkut sifat-sifat murni, yaitu sifat-sifat yang tidak mengandung suatu hubungan hakiki dengan materi, ruang dan waktu. Allah memiliki sifat-sifat itu secara formaliter dan eminenter, yaitu sesuai dengan 13 Edward Schillebeckx, Revelation and Theology, Vol. 2. Op. Cit., hlm. 181. 82 arti formal mereka dan tanpa pembatasan yang selalu ada pada barang ciptaan.14 Atribut, baik, benar dan hidup, mengenai Allah, itu berarti bahwa tidak hanya hal baik, benar dan hidup itu berasal dari Allah, tetapi juga berarti bahwa Allah itu sendiri adalah lebih baik, lebih benar dan lebih hidup, daripada apa saja yang ada. Atribut-atribut itu disebutkan mengenai Allah dan manusia menurut kodratnya masing-masing. Mengenai Allah disebut dengan atribut itu secara per naturam sedangkan disebutkan mengenai manusia secara per accidens. Untuk mengatakan per essentiam bahwa Allah itu baik, Allah itu benar dan Allah itu hidup, dan mengatakan bahwa ungkapanungkapan itu lebih dari sekadar metafora belaka, maka konsep kebaikan, kebenaran dan kehidupan itu haruslah mengandung suatu kemampuan untuk membentangkan hingga menandakan sesuatu yang mengatasi bidangnya sendiri sebagai representasi. Dalam kemampuan yang mengatasi representasi inilah letak penggunaan analogi dari bahasa insani mengenai Allah.15 Sedangkan analogia proportionalitatis impropriae di dalamnya ada relasi keserupaan tertentu antara kata yang kita kenakan pada pengalaman insani di satu pihak dan arti kata itu bila kita kenakan pada Allah di lain pihak, walaupun artinya sendiri tidak dipertahankan melainkan diubah menjadi kiasan. Analogi model ini umumnya mengenai perfectiones mixtae, yaitu mengenai kesempurnaan-kesempurnaan yang dari kodratnya sendiri masih mengandung ketidaksempurnaan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah terang maka ketidaksemprunaan tertentu dari terang disingkirkan manakala dikenakan kepada Allah. Dengan itu, kata itu mendapat arti yang lain dan yang sangat sesuai dengan realitas ilahi. 3.3. Manusia Mungkin Berbicara Tentang Allah Dengan analogi yang digambarkan itu, Skolastik bisa menjawab kesulitan yang muncul bahwa semua konsep manusia itu sejauh sebagai hasil tanggapan akal melalui dan bekerjasama dengan kapasitas sensitif, maka konsep itu tetap bersifat terbatas, sehingga sangat tidak sesuai untuk dikenakan kepada Allah yang tak terbatas dalam adanya. Kalau kita tetap 14 Bdk. Ibid., hlm. 194. 15 Bkd. Ibid., hlm. 195-196. 83 memakai konsep-konsep untuk membahasakan Allah, maka jelas hal itu tidak pada tempatnya dan sangat tidak tepat, sebab konsep itu selalu bersifat terbatas sementara Allah tak terbatas. Konsep sebagai sarana insani untuk mengatakan sesuatu tentang Allah adalah tidak memadai. Allah itu adalah realitas yang in ordine essendi melebihi segalanya. Itu benar. Akan tetapi akal kita terus-menerus berusaha menuju kepadaNya dalam aktus pengetahuan. Kita tidak memiliki gambaran tentang Dia, sebab kita tidak pernah melihat dari muka ke muka dan tidak pernah mendengar suaranya secara langsung. Tetapi kalau kita mau berpikir atau berbicara tentang Dia, maka kita, dalam hal itu, menerjemahkan dinamika akal kita, yang mentransendensikan segalanya itu ke dalam konsep-konsep, di mana konsep-konsep itu juga dipakai dalam pengalaman insani bahkan dipakai dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini Skolastik membuat distinksi yang tegas antara res significata yaitu apa yang diartikan atau dimaksud dan modus significandi yaitu cara kita mengartikan atau menunjukkan maksud itu. Adapun cara kita manusia untuk mengartikan atau menunjukkan Allah (gambaranNya) selalu kurang sempurna, akan tetapi apa yang kita artikan atau maksudkan itu adalah benar dan tepat, oleh karena didasarkan atas intuisi dinamika intelek manusia. Karena itu, semua istilah atau konsep tentang Allah hanya id quod significatur yang selalu bersifat kurang sempurna, sebab semua konsep itu hanya mengungkapkan satu aspek saja dan juga karena konsep itu tidak pernah bisa mengungkapkan yang konkret dan individual.16 Distinksi res significata dan modus significandi itu akhirnya bermuara kepada distinksi antara res significata (pengertian) dan res concepta (gambaran), dalam hal membahasakan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita bisa berbicara tentang Allah, maka itu berarti lebih sebagai membuat signifikasi tentang Allah daripada suatu representasi (konsep).17 16 Thomas Aquinas, De Potentia, 7, ad 14: “Illud est ultimatum cognitionis humanae de Deo quod sciat se Deum nescire, in quantum cognoscit, illud quod Deus est omne ipsum quod de eo intelligimus, excedere” (Paling jauh yang dapat diketahui oleh manusia ialah bahwa manusia tahu bahwa ia tidak mengenal Allah, sejauh ia tahu bahwa Allah melebihi apa saja yang dapat kita mengerti tentang Dia) 17 Bdk. Edward Schillebeckx, Revelation and Theology, Vol.2. Op. Cit., hlm. 170: “The res significata per nomen transcends the res ut concepta (or the ratio nominis or the significatio nominis). Nowhere does Aquinas assert that the significatio transcends the repraesentatio, because, with him, significatio always means the conceptual content.” 84 Dengan demikian, kita telah menyelesaikan soal inaedequatio antara “bahasa yang insani yang selalu terbatas” dan “Allah yang dibahasakan yang selalu bersifat tak terbatas”. Sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang Allah seperti dianut agnostisisme, karena mereka melihat pengetahuan itu melulu sebagai representasi.18 Gambaran itu selalu berhubungan dengan semacam objektivasi, yaitu hal bagaimana melihat hakikat Allah itu. Tidak mempunyai gambaran tentang Allah berarti tidak melihat apa Dia itu. Akan tetapi, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengetahuan semacam itu tentang Allah tidak mungkin bagi manusia. Manusia siapa pun, dalam keadaan bagaimanapun, sejauh dia sebagai makhluk ciptaan yang bersifat terbatas di atas dunia ini, tidak mungkin mencapai pengetahuan seperti itu. Seandainya pengetahuan semacam itu mungkin dicapai, maka itu berarti suatu pengetahuan univok. Dengan itu pula, Allah tidak lagi sebagai Allah, atau manusia tidak lagi sebagai manusia. Sebab pengetahuan univok itu menunjukkan keduanya harus setaraf, entah manusia menjadi setaraf dengan Allah, atau Allah menjadi setaraf dengan manusia. Yang jelas kita tetap mengakui bahwa secara ontologis adanya perbedaan antara Allah dan manusia. Namun perbedaan ontologis itu tidak membuat manusia menjadi tidak mungkin untuk mengenal Allah. Manusia, meski secara terbatas, tetap bisa mengenal Allah. Akan tetapi manusia mengenal Allah dalam transendensiNya hanya kalau manusia mengenal Dia sebagai tujuan terakhir dari segala sesuatu yang diketahui. Hal itu mungkin apabila kita telah memahami bahwa dalam setiap perbuatan kita, pengetahuan kita mentransendensikan objek yang terbatas dan yang membatasi pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, tidak benar bahwa istilah-istilah positif yang kita gunakan tentang Allah tidak memberikan pengetahuan positif tentangNya. Dengan demikian, manakala kita berkata bahwa Allah bijaksana dan baik, maka kita tidak hanya bermaksud bahwa Allah adalah sumber dari sifat-sifat ini dalam makhluk ciptaan. Hal ini tidak akan menerangkan banyak kepada kita tentang Allah sendiri, sebab kita tidak pernah berkata tentang Dia bahwa Dia adalah sehat, walaupun kita tahu bahwa Dialah sumber dari sifat ini pada makhluk ciptaan. 18 Bdk. Suzanne Cunningham, Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl, Neherland: Martinus Nijhoff, 1976, hlm. 58-75. 85 4. Penutup Tidak memberi hak kepada bahasa untuk berbicara tentang Allah sebenarnya akan membawa kepada penolakan begitu saja terhadap yang Mahamutlak pada taraf akal budi. Hal mana berarti pula bahwa wahyu menjadi tidak mungkin bagi akal budi. Kalau seorang teolog mengatakan bahwa wahyu itu adalah Sabda Allah, tetapi dalam arti apa Sabda Allah itu kalau bukan yang dimaksud juga adalah bahasa insani. Wahyu itu terjadi melalui mediasi bahasa manusia.19 Lalu dalam arti apa istilah-istilah yang berasal dari pengalaman insani itu dapat dikenakan kepada Allah? Menurut Skolastik, pengenaan bahasa manusia mengenai Allah bukan dalam arti univok yaitu dalam arti sama dengan arti yang dimiliki dunia pengalaman insani dan bukan pula dalam arti ekuivok yaitu pelbagai arti yang tidak mempunyai kesamaan sedikit pun, melainkan secara analog yaitu memiliki arti yang sama sekaligus beda. Dengan teori analogi itu mereka bisa mempertahankan transendensi Allah sekaligus partisipasi ciptaan pada Allah (participatio esse divini). Dengan itu, soal inadekuasi pengenalan dan pengetahuan manusia mengenai Allah yang berakibatkan bahwa kita tidak memiliki konsep mengenai Allah, dapat diselesaikan. Kita pun mampu membuat suatu konsep yang jelas bersifat positif dan distinktif tentang Allah. Demikian juga halnya terhadap keberatan yang mengatakan bahwa kalau manusia mampu berbicara mengenai Allah berarti manusia tidak setia kepada Allah, bisa dijernihkan. Kepada mereka yang berpendapat demikian kita harus mengatakan bahwa tidak berkata-kata tentang Allah adalah mengkianati pengalaman yang mendorong kita untuk menyatakan dalam bahasa kehadiran terasa dari sang Mahamutlak. Di sini jelas bahwa pembicaraan manusia mengenai Allah sebenarnya memiliki aspek intelektual yang penuh arti, yaitu menyangkut martabat roh manusia ke taraf transkonsepsional, sehingga ia bisa tiba kepada yang tak terungkapkan. Dasar antropologis kemampuan transkonsepsional ini adalah kerohanian manusia. Dalam diri manusia terdapat suatu kapasitas rohani 19 Bdk. Edward Schillebeckx, Church. The Human Story of God, London: SCM Press, 1990, hlm. 15: “In that case revelation is talk of God, the “Word of God, which is proclaimed to human beings straight from heaven. But that raises the critical question how “revelation” can be perceived and thus meaningfully affirmed by men and women, especially without human experience”. 86 untuk melampaui dirinya justru karena dia tidak merupakan materi belaka. Dasar antropologis itu sangat sesuai dengan apa yang disebut epistemologi logos20 dalam teologi Kristen bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rasional yang menjadikan manusia bisa berpikir dan berbahasa. Bahasa manusia itu menjadi mungkin tentang Allah karena manusia adalah ciptaan Allah, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambarNya sendiri. Secara teologis kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya karunia kemampuan berbicara dan berbahasa tentang Allah menggambarkan imago dei, khususnya rasionalitas. Karena itu, kecukupan bahasa manusia untuk berbicara tentang Allah yang transenden bersandar pada theomorfisme21 manusia yang telah Allah jadikan sebagai pengguna bahasa, yang mampu menerima komunikasi linguistis Allah dan merespons dengan cara yang sama.22 Akan tetapi, kemampuan transkonsepsional itu tidak hanya melibatkan aspek intelek melainkan juga aspek etik sebagai dimensi moral roh manusia yang lebih eksistensial sifatnya. Justru pembicaraan mengenai Allah tidak dapat memperoleh pembenarannya kecuali dalam pengakuan yang lebih menyeluruh yang mendahului pembicaraan sendiri dalam manusia. Norbertus Jegalus: Dilahirkan di Manggarai, Flores, NTT, 23 Juni 1962, meraih gelar Magister Artium (MA) dalam Bidang Filsafat pada Hochschule für Philsophie S.J, München, Jerman (2000) dan Dr. phil. (Doctor philosophiae) dalam Bidang Filsafat Politik pada Ludwig-Maximilian-Universität, München, 20 Bdk. Paul Budi Kleden, “Perkawinan Baru Antara Iman dan Akal Budi: Mas Kawin yang Terlampau Mahal”, dalam, Jurnal Ledalero, Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol 6, No. 2, Desember 2007, hlm. 179: “Mengatakan bahwa manusia sendiri mampu menggapai kebenaran adalah satu pengingkaran terhadap ciri keterciptaannya. Padahal di pihak lain, menyerah kalah di hadapan keterbatasan ciptaan ini dan menolak sama sekali kebenaran dari lingkungan manusia, akan membawa kepada diktatur relativisme. Jawaban di dalam dilema ini adalah inti iman akan Allah sebagai kebenaran, Logos, sebagaimana dikatakan dalam Prolog Injil Yohanes”. 21 Gordon H. Clark, Religion, Reason and Revelation, Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1961, hlm. 135. 22 Bdk. Edward Schillebeckx, Revelation and Theology, Vol. 2. Op. Cit., hlm. 278280. 87 Jerman (2008), dengan Disertasi: Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion, untersucht am Beispiel der Pancasila (München: Herbert Utz Verlag, 2009). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Filsafat Agama, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. DAFTAR RUJUKAN Aler, Jan, “Heidegger’s Conception of Language in Being and Time”, dalam: Joseph J. Kockelmans, On Heidegger and Language, Evanston: Northwestern University Press, 1986. Aquinas, Thomas, De Potentia, 7, ad 14. Aquinas, Thomas, Summa contra Gentiles I, 34. Aquinas, Thomas, Summa Theologia I, q. 13, a.5 dan 6. Baillie, John, The Ideas of Reveraltion in Recent Thought, New York: Columbia University Press, 1956. Barth, Karl, Churh Dogmatics, Vol. II: The Doctrine of God, ed. G.W.Bromiley & T.F. Torrance, New York: Scribner, 1957. Clark, Gordon H., Religion, Reason and Revelation, Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1961. Cunningham, Suzanne,Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl, Netherland: Martinus Nijhoff, 1976. Dewart, Leslie, The Future of Belief. Theism in a World Come of Age, London: Burn & Oates, 1967. Jegalus, Norbertus, Metafisika Dasar, Materi Kuliah Tatap Muka pada Fakultas Filsafat Agama, Universitas Widya Mandira, Kupang, 2009. Kaufmann, Gordon D., God the Problem, Cambridge: Harvard University Press, 1972. Kockelmans, Joseph J., “Language, Meaning, and Existence, dalam: Joseph J. Kockelmans, On Heidegger and Language, Evanston: Northwestern University Press, 1986. Nash, Ronadl H., Firman Allah dan Akal Budi Manusia (terj. Sulyani Wiryo), Surabaya: Penerbit Momentum. 88 Paul Budi Kleden, “Perkawinan Baru Antara Iman dan Akal Budi: Mas Kawin yang Terlampau Mahal”, dalam: Jurnal Ledalero, Wacana Iman dan Kebudayaan, Vol 6, No. 2, Desember 2007. Schillebeckx, Edward, Church. The Human Story of God, London: SCM Press, 1990. Schillebeckx, Edward,Revelation and Theology, Vol. 2. London: Sheed and Ward, 1987. Temple, William, Nature, Man and God, New York: St. Martin’s Press, 1934. Verre, F., “Analogy in Theology”, dalam: P. Edwards (ed), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. I, New York-London, 1967. 112 to moral realities? The correct balance between faith and reason is actually a spiritual moral reality, not a physical one. Where could we find the res of spiritual and moral realities? There is a res that we can find within man himself. It is res even though it is in man because it is a given. It is not something that is left to the free choice of man or subject to his intellectual creativity. This internal res is his human nature9. This human nature is full of drives, appetites and faculties that reach out to other persons and external reality, for man was made in order to interact with other persons and the world. His human nature also sets some basic rules regarding the correct way in which man could relate to others and the world, for his relating with other people and external reality is governed by freedom. Human creativity can build up or destroy. Man could hate and man could love. This range of possibilities of human action falls under the scope of his freedom. This is the reality of morality. When it comes to the external physical world, the mind grasps what is, i.e, what is there and what has being. The being of things external to man is the basis for the truth of our knowledge of the external reality, which is the adaequatio rei et intellectus. On the other hand, moral realities do not refer to what is, strictly speaking, although moral realities need a foundation of physical realities such as the body of the person and the other people and the physical things he relates with. Moral realities refer to what should be, not immediately what is. Therefore, moral realities refer to an ought.10 A moral object is not merely a physical thing. It is the manner in which the person relates with other persons and/or with his environment. There are correct ways of relating or interacting with other persons and the environment and there are incorrect ways of relating or interacting with them. Even though it is a way of acting and not a physical thing, still it is a res and could enter into the dynamics of truth as embodied in the adaequatio rei et intellectus. We can, therefore, now see that there is a speculative truth or a truth which is the conformity of the speculative mind with a being, and there is a 9 We have returned to human nature as we promised at the end of the section entitled The Golden Mean. 10 RHONHIEMER, Martin, Ley Natural y Razón Práctica: una Visión Tomista de la Autonomía Moral, EUNSA, Pamplona, 2006, p. 31. 113 moral truth, which is the conformity of the practical mind with the natural inclinations or ends of man. Man becomes good when his practical mind or practical intellect leads him to achieve the ends dictated by his nature, and he becomes bad when he veers away willingly from the ends which were set by his nature. This is so because reaching one’s end or achieving one’s goal is equal to perfection. If you are able to accomplish what you are supposed to do, then you can be considered perfect. If a bowman is able to hit a bull’s-eye with his arrow, then he can be called a perfect bowman. If a bird is able to sing the song that belongs to its nature, then it has reached its perfection as a member of its species. Man becomes perfect when he is able to achieve the goals set by his nature, which in the end are the goals set for him by his Creator. But moral goals are more complex than physical goals. Physical goals a more concrete: e.g., for a bird to build a certain type of nest, for an animal to be able to eat the type of food for which it was made, etc. When it comes to the moral activity of man, the actions can be very varied, even though all of them may be called “good”. Thus, a man does not necessarily become better than somebody else just because he has quantitatively achieved more than his fellowman. Some achieve more, some achieve less. Some achieve this and some achieve that. But goodness embraces a great variety of good actions. Thus, you can have many men with very varied achievements and all of them can be good, all of them can sufficiently achieve their perfection even though their activities may have been varied. Goodness is a qualitative feature of man, not a quantitative one. With the above explanation, we just wanted to show that several types of actions and achievements can actually fit into the natural ends of man. This is why men can achieve perfection in different ways. Still the res, which is the moral object or goal, remains the same and still has to be fulfilled. To be morally good, man has to choose to fulfill the moral dictates of his nature. The natural moral goals set for man so that he can achieve his personal perfection are embedded in his human nature. These goals are spiritual and, therefore, they are not constraining, because they are open to a wide variety of possible achievable goods both material and spiritual. The achievement of these goals makes a man good. Their non-achievement makes him bad. When one of the natural human goals is not achieved then there is a yawning gap 114 in his being, and he is imperfect. His imperfection can be felt and this causes unhappiness. The collection of all the natural human goals from the moral point of view makes up the human natural law. It is universal for all men regardless of sex, race, creed or social status. It is required of everyone. Their achievement makes everyone and anyone happy. Thus if we are to ask what is the basis for the medium virtutis, for the recta ratio agibilium and for the adaequatio rei et intellectus in man, we can readily say that it is human natural law. Human natural law is very basic and is true for all. With this we can now answer the very first question that we asked: How do we achieve harmony between faith and reason? Answer: By identifying the medium virtutis, the recta ratio and the moral res as it is dictated by human natural law. The importance of the universality of human nature and human natural law can be seen in the worldwide concern for the universal declaration and th respect for human rights. After the Second World War, the world saw the need to establish and agree upon what each and every man, regardless of sex, race or creed, has a right to have or do. The Second World War saw the horrors of the holocaust. According to the laws of their own nation, justice could not be served to the perpetrators of this horrible project because the laws of the nation to which they belong would not convict them. The question then arises: Are these people not responsible just because the laws of their country do not condemn them? Are they not answerable to the victims of their doings? To almost all men on earth, the reply to that question is “yes”, they are responsible and they have to make up for these crimes. Since these are not crimes in their own nation, where can they become crimes? Can someone who has committed a horrendous act that is not a crime in his own country be lawfully judged in another country where that specific act is a crime? Would that fulfill all justice? It is at this point that the world suddenly realized that there such things as “crimes against humanity”. These are crimes no matter where the perpetrator does it. These are the infringement of rights no matter what nationality or other circumstances a person may have. These are an indication that there indeed is a universal human natural law, that all human beings on earth are indeed equal because they have one and the same nature which is the basis for all their universal human rights. 115 6. Truth and Religion For faith or religion to be imbued with reason—for faith to be reasonable—, it has to be true. It has to be true in relation to the external world of being, which is the is, and it has to be true in relation to the internal truth of human natural law, which is the ought. If we set ontological and moral truth as conditions for faith to harmonize with reason, we might get into a lot of trouble. What is true about those things that we do not have empirical data of? I was once reading a textbook of basic philosophy required for all students in a university in the Philippines, and in one of the lessons it said that God is a fictitious concept. This they said because there is no empirical data of God. No empirical data that could be scientifically tested, a principle which Karl Popper (1902-1994) has popularized as the criterion of falsifiability.11 The criterion of falsifiability is supposed to determine which is scientific and which is not. Of course, the criterion for falsifiability is fine. But there is one problem. In this day and age, when we say that something is “scientific”, that is taken to be the equivalent of saying that that thing is true. As a corollary, anything that is non-scientific is not true. Now take God. Since he does not have empirical data and cannot be falsifiable, then he is not scientific. Does it therefore mean that God is not true since He is non-scientific? This is the gist of the controversy on the theory of Intelligent Design which some people in the United States, among the many scientists, are trying to propose as an alternative to the Darwinist evolutionary theory of the origin of life that is the standard required science education fare in American schools.12 Darwinist evolution has always been considered scientific, apparently because it is falsifiable. But the main cause of life proposed by the theory of Intelligent Design, that is, the Supreme Universal Being, Creator of all life, is not falsifiable and, therefore, not scientific. If God is non-scientific, then God is probably not true. The lack of empirical data about God is also the reason why Kant does not consider the idea of God scientific. For Kant, what is scientific is 11 THORTON, Stephen, “Karl Popper”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/ archives/sum2009/entries/popper/>. 12 There is a lot of literature on Intelligent Design that the reader can easily access. This author recommends Chance or Purpose? Creation, Evolution and a Rational Faith by Schonborn, published by Ignatius Press. 116 the intelligent ordering and structuring of chaotic phenomena by our mental categories, especially in the realm of man’s pure reason. Empirical data plus intelligent order is the formula for science. For Kant, these are the synthetic a posteriori judgments: “The truth of empirical judgments is the bottom-level sort of truth for Kant, in that all of the other kinds of truth presuppose it”.13 God, therefore, can come into the cognitive picture when we move into the realm of practical reason, where He is a postulate together with the world and the soul so that the mind can make a synthesis of all the external and the internal experiences of human knowledge.14 But He has no role in the pure reason. So, is God only a postulate? Is God non-scientific? Is He only an abstract guide for our moral behavior or does He really exist? Is He true? The question of the existence of God is related to the question of the validity of Metaphysics15 as a body of true knowledge. In Medieval philosophy, the metaphysical world was accepted as part of the real world: spirits existed; immaterial principles compose and move the material realities that we find in this world. Starting from Descartes, a dividing line was drawn between the empirical world and the world of thought. Kant eliminated the empirical world and reduced it to phenomena in the mind, but he also reduced the once considered metaphysical realities into mental categories, and God the world and the soul into postulates. After that the allergic reaction to metaphysics as knowledge grew and became widespread. Nowadays, Metaphysics is considered as imagination, fantasy, abstraction, myth but never as truth. Metaphysics is non-scientific. 13 HANNA, Robert, “Kant’s Theory of Judgment”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), 1.3, Edward N. Zalta (ed.), <http://plato. stanford.edu/archives/sum2011/entries/kant-judgment/>. 14 ROSSI, Philip, “Kant’s Philosophy of Religion”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), 3.5, Edward N. Zalta (ed.),<http://plato. stanford.edu/archives/win2011/entries/kant-religion/>. 15 The world “metaphysics” comes from the two Greek worlds meta, which means “beyond” and physis, which points to Nature, meaning physical nature. Anything metaphysical would be something that is beyond physical nature. If you believe that only physical nature exists, then what is metaphysical does not exists. It would only exist as a creation of our mind. If you believe that not only the physical order but the spiritual order also exists, then metaphysical things will be real to you, and this includes God and the soul. 117 But did it ever to occur to you that God is a metaphysical reality? There many other metaphysical realities that many people commonly accept as real and part of everyday life: the soul, thought, life, Beauty itself, Goodness itself, perfect justice, happiness, love, freedom, etc. There could never be perfect justice here on earth, and yet we yearn for and believe in perfect justice. That was what the Communists thought they could achieve here on earth. But no Communist nowadays is openly preaching about this promised early heaven. If you look closely at freedom, you will find that it is not only a matter of the absence of obstacles to doing whatever you want. Even with freedom, you cannot do anything that you want. The concept of freedom is much more than the absence of obstacles to the decisions of the will. It involves making the right choices, and man often chooses not because of empirical reasons but because of spiritual ones. Of course, the empiricists and materialists might argue that even these things which we call “metaphysical” or “spiritual” can be explained away by empirical, physical, chemical or biological processes. But this is claim is only a promise that in the future it might be like that. There is no proof yet that everything metaphysical or spiritual can be completely reduced to the physical, chemical or biological. In fact, for many people, it is rather the contrary: the metaphysical cannot be reduced to the physical, chemical or biological. The metaphysical is another type of reality, even though it relates perfectly with and not separated from the physical reality. If we are right about the existence of the metaphysical world vis-àvis the physical world, then reality is composed of two realms that mutually require each other: the empirical world which is true and the spiritual world which is also true. This is inconceivable for a materialist scientist. But for once perhaps we should rethink their insistence on the point that only the empiricists and the materialists have a right to determine what is true. Our spiritual experience as human beings dealing everyday with love, beauty, justice and freedom seems to say that empiricism and materialism are not enough to explain the world. There’s more to this world than meets the eye. The realities of religion dwell within the metaphysical realm: God, love, salvation, mercy, sin, etc. Many of the metaphysical realities can also be known through philosophy, and not by faith alone, as for example, beauty, 118 forgiveness, goodness, being, etc. Our reason can travel into the metaphysical world. Our reason does not only know the empirical but also the metaphysical and spiritual. Our reason can do this because both the empirical and the metaphysical are true, and the object of reason is the truth. Both empirical reality and metaphysical or spiritual reality are valid objects for our knowing because they are true, they are real. If we accept the existence of the mystical and the sublime, within the metaphysical or spiritual world, there are also two realms: (1) the philosophical realm that is within the reach of human reason as it goes with its human power alone and (2) the supernatural realm which, as it name implies, is beyond the reach of the natural power of the human reason alone. This is another idea that each and every man will have to sift carefully in his mind in order to see its logic and the fittingness of its existence. If man is not the creator of the world and does not define the world, then the world is bigger than man. If man cannot explain himself and does not originate from himself, there has to be a field of reality that is greater than man. If man cannot acquire existence by himself, then he will have to be given existence by Another. And the one that should give him existence must be greater than man. If the Creator of man is greater than man, then there must be aspects of the Creator and all things related to him that are beyond the human capacity to grasp. If man can fully understand everything about his Creator, then this will give us the impression that the Creator is not that powerful and wonderful after all. It might make us think that the Creator is just a little step away in perfection in relation to our species, homo sapiens. Would Creator be like that? Would everything about a Creator fit perfectly into man’s capacity to understand? Could a real Creator be completely embraced by the investigative arms of science? It does not seem so. The religions of the world attest to this. Man constantly admits his limitedness because his limitedness is a constant and well-apparent experience for him. Those who reject religion reject it because they could not understand why anything could escape the piercing scrutiny of man’s intellect. But the believers of this world think otherwise. If the believers of this world are right then, aside from the philosophical realm, there is a supernatural realm that is a place16 that is more exclusively 16 We are using the word “place” here, but we do not mean a physical place. For pure metaphysical realities are immaterial and do not need a place to reside in. 119 God’s. It is a place that is obscure to man that still lives in this world. But it is a place which can be known by man if he is allowed by God, that is, if God reveals this “place” to him, if God tells man what this “place” contains. This is what Revelation is all about, and most world religions tell of some revelation of the Divine. God goes out from “His place” and enters “man’s place” so that man could “see” Him. Man then receives new knowledge that he would never have achieved if God did not take the initiative. Now the content of Revelation could not be used in philosophy, for that is knowledge that we would not normally have if we are not given the opportunity by God, but the idea that there is a “cognitive place” that is beyond the ability of the human mind can enter into philosophical investigation. Recall the fact that the very name “philosophy” indicates the existence of a realm of knowledge that is beyond man’s ordinary ability to know. Instead of calling philosophy sophia which means “wisdom”, it is called philosophia, which means “love for wisdom”. Why should it be “love for wisdom” and not “wisdom” itself? Why could we only aim to love wisdom and not achieve wisdom itself? It must be because the real wisdom is beyond this world. The fullness of wisdom can only be achieved if we are to reach the place of God. This is what Socrates and Plato thought and believed. This was why Socrates was look forward to death, as we are told in the dialogue Phaedo, because after death he was expecting to see the Ideas that constituted the perfection of knowledge, Wisdom, the achievement of which mean the most perfect happiness. The material or empirical world is intelligible. The philosophical world is intelligible. The supernatural world is intelligible. Here we find the compatibility between faith and reason. Faith resides in the supernatural world and reaches out to man in the empirical and the philosophical world. Man meets faith through revelation and finds out that his intellect can grasp a greater part of the message that is revealed to him. His mind enters the supernatural realm and then his heart yearns to live there for he realizes that there is Someone there who loves him and cares for him. Metaphysics is the bridge between the empirical world and the supernatural world, which is the world of religion. If metaphysics is rejected, We are just using the word “place” to signify that God is unreachable for the knowing faculties of a man who is still in this world. 120 then only the empirical can be real. If metaphysics is rejected, religion will become a mere product of the human mind or of human feeling. Metaphysics falls within the realm of philosophy and reaches out into the supernatural realm. Philosophy is not theology. Theology takes Revelation as its premise, but philosophy can only argue logically from man’s ordinary experience. But man’s experience is not only empirical but spiritual and metaphysical as well. The supernatural, which is realm of religion and faith, is also spiritual, but it is beyond the scope of philosophy. Metaphysics is used in both philosophy and theology, so here we find the bridge between the upper limits of our reason and the lower limits of the reality of God. 7. Imagine There’s a Heaven There’s as song made famous by John Lennon whose title is Imagine. Its melody is soothing and captivating, the cadence of its lyrics has a pleasing effect on the soul, and its words talk about peace and brotherhood, which makes it exceedingly attractive to those who drink up its music. But it is a song against religion. Pay attention to its lyrics: Imagine there’s no heaven. It’s easy if you try. No hell below us. Above the earth just sky. Imagine all the people living day to day. The invitation to “imagine all the people living for to day” implies that we should not worry about what’s going to happen to us after this life because nothing is going to happen to us. There is no heaven to look forward to. There is no hell to punish you. There is no heaven. That’s just the sky. The denial of the relevance of the after life and the nonchalant attitude towards reward and punishment for the good or evil we have done is an echo of what we find in the lyrics of the song I Got Plenty o’ Nuttin from the musical Porgy and Bess: “I ain’t a’frettin bout hell till the time arrive. Never worry long as I’m well. Never one to strive to be good, to be bad. What the hell? I’m so glad I’m alive!” The “now” is what is relevant. There is nothing waiting for you in the afterlife. Imagine there are no countries. It isn’t hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion, too. Imagine all the people living life in peace. Lennon leads you to think that the establishment of countries and religion is the cause of killing because country and religion are things one has to die for. The implication is that nationalism and religion are the cause of war and 121 strife. If only there were no nations and religion, we would all live in peace. Of course, the song presents no proof that nations and religion incite war and drive people to kill. There is no argumentation. The beauty of the music and the speciousness of the words lull you into believing the message. The song Imagine is a plug for Communism. Just look at its third stanza: Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Communism during that time was thought to be the solution to the world’s woes. But later revelations of the horrors that were happening inside Russia, China, Czechoslovakia, Poland and East Germany proved otherwise. This was the result of imagining that there’s no heaven. Now imagine that there really is a heaven. Imagine that there is a God whom we should know, love, worship and glorify. Wouldn’t that also lead to love and peace? Or rather, isn’t the religious scenario a more logical framework for peace and harmony than the Communist scenario? Just look at how Poland survived the Communist intrusion: it was through religion. According also to a survey made by this author for a international conference at the Atma Jaya Univeristy in Yogyakarta just this September 2011, the successful and peaceful outcome of the 1986 EDSA People Power Revolution in the Philippines was made possible thanks to religious leadership.17 Does religion destroy or does it build? Does it weaken or does it strengthen? Is it reasonable or unreasonable? Thomas Aquinas says that there are two aspects of man that form part of his essence, that are part of human natural law. These are: (1) his social nature and (2) his religiosity. By nature, man is supposed to live in society. He cannot easily achieve his proper perfection without the help of other human beings. Man is supposed to grow in an environment where other people live with him and provide him with institutions that nurture his body and develop his spirit: schools, churches, art, music, business, industry, etc. Without society, man cannot be man. 17 NADRES, Ramon, Leaderless Change? : a Comparison Between the Arab Spring and the 1986 EDSA People Power Revolution in the Philippines, a paper presented at the International Conference on Social Media Cultures, Faculty of Social and Political Sciences, University of Atma Jaya, Yogyakarta, 22 September 2011. 122 But Thomas Aquinas also says that man is naturally called to establish a relationship with God, with his Creator. Man is religious by nature. An atheist is a queer bird. There is a part of his nature that is not fulfilled. By this we see that human natural law is really the basis for the harmonization of faith and reason. By knowing the ins and outs of our nature, we can discover our calling to faith. By knowing our human nature, we can have the criteria to judge whether the way we live our faith right now is compatible with both speculative and practical truth. Reason looks at and understands our human nature and then turns around and judges all that we believe and practice on the basis of the knowledge of the truth about human nature. How can the terrorist turn away from the violence he advocates in the name of religion? By using his intellect and realizing that violence is incompatible with faith because it is incompatible with the very nature of God and the very nature of the soul. This is what Pope Benedict the XVI wrote in his Regensburg Lecture in 2006: “The Emperor [Manuel II], after having expressed himself so forcefully, goes on to explain in detail the reason why spreading the faith through violence is something unreasonable. Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul. ‘God,’ he says, ‘is not pleased by blood—and not acting reasonably is contrary to God’s nature. […] [The Emperor] continues: ‘Faith is born of the soul, not the body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason properly, without violence and threats…. To convince a reasonable soul, one does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of threatening a person with death.’”18 How can the violent atheist turn away from his path? What could have stopped Robespierre, the Jacobins and the Committee on Public Safety from carrying out The Terror? If only they realized that religion is very reasonable. With the same coin, we can bring before the atheist the words of Emperor Manuel II above: “Faith is born of the soul, not the body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason properly, without violence and threats…. To convince a reasonable soul, one does not 18 BENEDICT XVI, Regensburg Lecture, 12 September 2006, no. 13 (as translated and quoted in SCHALL, James V., The Regensburg Lecture, St. Augustine’s Press, Indiana, 2007, p. 41. 123 need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of threatening a person with death.” Knowledge of what human nature truly is, of what it requires of us, is the key to harmony between faith and reason. Our faith has to become reasonable and our reason has to become faithful and religious. Man is naturally reasonable and man is also naturally religious. The unreasonable man and the irreligious man is an aberration. 8. Conclusion We started our investigation with the observation that extreme fideism and extreme rationalism are both unacceptable. They are stances that do not hold water and cannot stand up to the truth. That said, we proceeded in trying to find out where the truth lies and realized that, since faith and reason are not contradictories but contraries, there must be some way by which the two would harmonize. Through the teachings of Thomas Aquinas, we found out that there is such a thing as a golden mean, a medium virtutis, between two moral extremes. We then asked ourselves how we could arrive at that medium virtutis. The definition of prudence, the virtue by which we could correctly determine the medium virtutis, led us to the recta ratio agibilium. The very words of this definition tell us that secret to achieving the balance between faith and reason is in reason itself. But if reason depends on itself only, we know that we could very well fall into subjectivism and have no firm reference point on which we could anchor our decisions on what is right or wrong, on what is correct or not, on how the harmony between faith and reason could be achieved. We then realized that that firm reference point is the human nature of man, which later expresses itself as human natural law. Human natural law, according to Thomas Aquinas, tells us that man is a social being and that man is religious by nature. This leads us to conclude that man cannot be naturally and atheist, his very nature spurs him on towards the search for his Creator. At the same time, he is reasonable by the mere fact that his Creator had given him an autonomous reason with which he could analyze the truth of this world and arrive at the existence of his God. 124 The knowledge that bridges empirical knowledge in man with the knowledge that we could get on the faith is metaphysical knowledge. We therefore conclude that the acceptance of a metaphysical philosophy is the key to the harmonization of faith and reason. Without it, faith and reason remains isolated from other. Faith and reason would not be able to understand each other and conflict would ensue. In this day and age, therefore, when we want to achieve peace between faith and reason, we need to take up metaphysical philosophy again to achieve this goal. Ramon Nadres Born in Quezon City, Philippines, in 1998 Ramon finished his studies in the licentiate program in Ecclesiastical Philosophy at the University of Navarre in Navarre, Spain. His doctorate was finished in 2009 with the dissertation La Memoria en Santo Tomàs de Aquino: Fuentes y Originalidad at the University of Navarra, Spain with a Summa Cum Laude. At present, Ramon is the philosophy lecturer at the Faculty of Philosophy, Unika Widya Mandala Surabaya. His e-mail is [email protected]. BIBLIOGRAPHY ALVIRA, Rafael, La Razón de Ser Hombre: Ensayo acerca de la Justificación del Ser Humano, Ediciones Rialp S.A., Madrid, 1998, pp. 180-194. ARTIGAS, Mariano, Ciencia, Razón y Fe, EUNSA, Pamplona, 2004, pp. 157-172. ________, Filosofía de la Ciencia, EUNSA, Pamplona, 2009, pp. 250-275. COPLESTON, Frederick, A History of Philosophy, Volume II: Medieval Philosophy, From Augustine to Duns Scotus, Doubleday, New York, 1993, pp. 302-434. CORAZÓN GONZÁLEZ, Rafael, Filosofía del Conocimiento, EUNSA, Pamplona, 2002, pp. 139-185. FERNÁNDEZ, J. Luís and SOTO, María Jesús, Historia de la Filosofía Moderna, EUNSA, Pamplona, 2006. 125 GARCÍA CUADRADO, José Ángel, Antropología Filosófica: Una Introducción a la Filosofía del Hombre, EUNSA, Pamplona, 2008, pp 231-243. GARCÍA LÓPEZ, Jesús, Metafísica Tomista: Ontología, Gnoseología y Teología Natural, EUNSA, Pamplona 2001, pp. 97-159, 311-428 GILSON, Étienne, God and Philosophy, Yale University Press, London, 1941. _______, The Unity of Philosophical Experience, Ignatius Press, San Francisco, 1937. HANNA, Robert, “Kant‘s Theory of Judgment”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), 1.3, Edward N. Zalta (ed.), <http:// plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/kant-judgment/>. MARITAIN, Jacques, The Degrees of Knowledge, University of Notre Dame Press, Indiana, 1995, pp. _______, Natural Law: Reflections on Theory & Practice, St. Augustine’s Press, South Bend, Indiana, 2001. MORALES, José, Filosofía de la Religión, EUNSA, Pamplona, 2007. PIEPER, Josef, Guide to Thomas Aquinas, Ignatius Press, San Francisco, 1962, pp. 133-161. PINCKAERS, Servais, The Sources of Christian Ethics, The Catholic University of America Press, Washington, 1995, pp. 400-468. RATZINGER, Joseph, Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions, Ignatius Press, San Francisco, 2004. RHONHEIMER, Martin, Ley Natural y Razón Práctica: una Visión Tomista de la Autonomía Moral, EUNSA, Pamplona, 2006. _______, “Sulla Fondazione di Norme Morali a Partire dall Natura”, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 4 anno LXXXIX, Ottobre-Diciembre 1997, pp. 515-535. ROSSI, Philip, “Kant‘s Philosophy of Religion”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), 3.5, Edward N. Zalta (ed.),<http:// plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/kant-religion/>. 126 SCHALL, James V., The Regensburg Lecture, St. Augustine’s Press, Indiana, 2007. SARANYANA, Josep-Ignasi, La Filosofía Medieval, EUNSA, Pamplona, 2007, pp. 271-304. THOMAS AQUINAS, De Veritate, version found at www.corpusthomisticum. org. ______, De Virtutibus, version found at www.corpusthomisticum.org. ______, Sententia de Sensu et Sensato, version found at www. corpusthomisticum.org. ______,Sententia Ethicorum, version found at www.corpusthomisticum. org. ______, Sententia Metaphysicae, version found at www.corpusthomisticum. com. ______, Summa Contra Gentiles, version found at www.corpusthomisticum. org. ______, Summa Theologiae, version found at www.corpusthomisticum.org. ______, Super Sententiae, version found at www.corpusthomisticum.org. THORTON, Stephen, “Karl Popper”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford. edu/archives/sum2009/entries/popper/>. YEPES STORK, Ricardo, Fundamentos de Antropologá: un Ideal de la Excelencia Humana, EUNSA, 1977, pp.125-182, 467-500. 127 HUBUNGAN WAHYU DAN AKAL DALAM TRADISI FILSAFAT ISLAM Mukhtasar Syamsuddin Abstract This paper attempts to represent the world of philosophical thinking on the relationship between faith and reason among moslem scholars and Islamic doctrines. Qoran is the fundamental principle in inspiring any attempt of reason to find the truth. It means that reason still has its place and possibility to find the truth based on the truth of faith which is inspired by Qoran. It is the focus of discussion between the two outstanding moslem scholars, Ibnu Rusyd (520 H/ 1126 A-595/ 1198) and Ibnu Taimiyyah (662/ 1263). Ibnu Rusyd approaches the correlation between faith and reason in the term of relationship (ittisal). Meanwhile, Ibnu Taimiyyah explores the correlation between faith and reason under the term of muwafaqat. These two scholars are different with one another especially in exploring the fundamental meaning of reason (’aql) and revelation (al-naql). Keywords Revelation. Reason. Philosophy. Islam Philosophy. Religion. Dogma. Doctrine. Truth. Validity. Abstrak Tulisan ini bermaksud menggali kembali bagaimana alam pemikiran filsafat menjelajah di balik doktrin-doktrin agama Islam yang memutlakkan pertautan wahyu dan akal. Penggalian kembali ini beranjak dari kritisisme epistemologis Islam yang memandang bahwa sejatinya tidak ada dikotomi antara wahyu dan akal dalam tradisi filsafat Islam. Jika Al-Quran sebagai wahyu, sebagaimana epistemologi Islam mengartikulasikannya sebagai sumber inspirasi bagi akal dalam menemukan kebenaran, maka bahwa akal memiliki kedudukan penting dalam wilayah agama-Islam dengan sendirinya tidak dapat dipungkiri. Untuk “menemu-kenali” dan membuktikan pertautan itu, dalam tulisan ini 128 digunakan pendekatan historis-komparatif yang mengungkap khazanah pemikiran Islam dengan bertumpu pada dua filosof Muslim terkemuka, yaitu Ibnu Rusyd (520 H/ 1126 A-595/ 1198) dan Ibnu Taimiyyah (662/ 1263). Dalam mendekati persoalan wahyu dan akal, Ibnu Rusyd menggunakan prinsip hubungan (ittisal). Sementara prinsip kesesuaian Ibn Taimiyyah yang berarti wahyu dan akal tidak bertentangan tercermin dalam argumen-argumennya yang menggunakan terma muwafaqat. Meskipun implikasi makna terma ini hampir sama dengan prinsip hubungan (ittisal) dalam pandangan Ibnu Rusyd, namun prinsip-prinsip yang digunakan berbeda, terutama ketika keduanya memaknai akal (’aql ) dan dalam menjabarkan wahyu (al-naql). Pada prinsipnya kedua filosof memandang wahyu dan akal tidak bertentangan. Ibn Rusyd tidak saja dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa sains dan filsafat bertentangan dengan agama, sementara sasaran perhatian Ibnu Taimiyyah ditujukan pada pemahaman masyarakat tentang agama Islam yang menurutnya telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin sufisme, teologi, dan filsafat. Kata-kata kunci Wahyu. Akal. Filsafat. Filsafat Islam. Teologi. Agama. Dogma. Doktrin. Kebenaran. Kesahihan. 1. Pengantar Tradisi filsafat Islam, dalam tulisan ini diartikan sebagai model pemikiran yang memperoleh sumber inspirasinya dari dogma-dogma Islam dan merupakan hasil dari kesadaran historis yang telah melembaga berabadabad lamanya di dunia Islam. Sementara itu, upaya menjelaskan kembali bagaimana hubungan wahyu dan akal yang di dalam sejarah pemikiran ke-Islaman telah didiskusikan secara lebih detail dipandang sebagai domain filsafat agama yang mengangkat persoalan-persoalan fundamental epistemologis, misalnya apakah keimanan atau kepercayaan terhadap sesuatu harus dijelaskan melalui dalil akal (aqliyah) dan akal memberikan peran penting di dalamnya? Ataukah sudah merupakan hal yang jelas sehingga tidak butuh lagi penjelasan akal. Atau keimanan berdiri di luar garis tatanan akal 129 dan tidak saling terkait? Singkatnya, bagaimana sesungguhnya hubungan wahyu dan akal jika ditelisik dari bingkai filsafat Islam? Sebagaimana epistemologi Islam mengartikulasikan al-Quran sebagai sumber inspirasi bagi akal dalam menemukan kebenaran, dan bahwa akal memiliki kedudukan penting baginya, dengan sendirinya al-Quran sebagai wahyu tidak dapat dipungkiri. Persoalannya kemudian adalah landasan filosofis apakah yang dapat dikemukakan untuk menerangkan arti penting kedudukan akal itu? Untuk menjawab persoalan ini, perlu dilihat bahwa pemikiran filsafat Islam telah melewati lima tahap perkembangan, yaitu; pertama, tahap diterimanya al-Quran oleh umat Islam sebagai satu-satunya jalan spiritual dan pedoman kehidupan, kedua, tahap yang ditandai dengan bangkitnya pemikiran-pemikiran yurispridensi dan teologi Islam yang secara khusus menunjuk pada munculnya empat mazhab/aliran besar, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hanbali, dan Maliki yang kemudian diikuti oleh aliran-aliran kecil seperti Sunni dan Syiah, ketiga, adalah kelanjutan atau bahkan imitasi dari tahap kedua di atas yang memunculkan pemikiran model tradisionalis dan konvensionalis di kalangan kaum Muslim, dan keempat, tahap yang ditandai dengan penolakan atas otoritas doktiner kaum yurisprudensial (fuqaha) dan sufisme,1 dan kelima, tahap pemikiran kontemporer yang ditandai oleh berkembangnya gerakan revivalisme keagamaan dan meluasnya ketertarikan pada ilmu dan teknologi.2 Genealogik model pemikiran filsafat Islam, mengikuti pandangan alJabiri (2003: xiii) dapat dibedakan menjadi dua wilayah: Timur (al Masyriq) dan Barat (al Maghrib).3 Dari wilayah Timur, pemikiran Islam bercorak khas 1 Termasuk dalam barisan penolak ini adalah Ibn Taimiyyah (1263-1328) dan muridnya Qayyim al Jauziyah (1350). Keduanya menolak sikap tunduk secara buta terhadap wahyu, kepercayaan berbentuk tahayul, dan kepatuhan-kepatuhan yang anti kritik. 2 Qodir mengintrodusir kelima tahap ini dengan mengindikasikan tahap pertama dan kedua sebagai masa kejayaan ilmu dan filsafat hingga akhir abad ke-XX, sedangkan tahap ketiga dan keempat sebagai era kemajuan pemikiran Aristotelian dan perlawanan terhadap tradisionalisme, sedangkan tahap kelima adalah masa emansipasi pemikir-pemikir Muslim dengan menggunakan ilmu dan teknologi sebagai kekuatan melawan kejumudan dan kemunduran. 3 Wilayah Timur (al Masyriq) meliputi Persia, Mesir, Irak, Syiria, Khurasan dan beberapa wilayah lain, sedangkan wilayah Barat mencakup Maroko dan Andalusia (Spanyol). 130 mengikuti pemikiran tokoh yang hidup di wilayah itu. Dalam bidang filsafat misalnya, ditemukan corak pemikiran khas Ibn Sina yang dapat dikategorikan sebagai representasi tradisi rasionalisme ketimuran dan beberapa tokoh lainnya dalam bidang yang berbeda-beda seperti al-Ghazali, al-Asy’arie, dan Syafi’i. Dari wilayah Barat, pemikiran para tokoh lebih berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang kelak sangat berpengaruh dalam perkembangan intelektual Islam sebagaimana ditampilkan oleh Ibn Hazm dan Ibn Rusyd dalam bidang hukum dan filsafat, serta Ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Islam. Terhadap pembagian kedua wilayah itu, beberapa pegiat khasanah pemikiran Islam, menurut al-Jabiri (2003: xiv) memiliki semacam konsensus yang menganggap filsuf-filsuf Muslim telah bekerja dalam paradigma para penafsir Aristoteles atau setidak-tidaknya pada tradisi Hellenistik. Padahal interpretasi dalam konsensus tersebut sesungguhnya telah ternodai oleh ajaran pokok aliran Neo-Platonisme, sebagai bentuk turunan pemikiran kepada filsafat Aristoteles dari pertimbangan yang salah atas karya Plotinus berjudul “Enneads”. Sejauh itu, al-Jabiri (2003: xiv) mengoreksi konsensus tersebut dengan menunjukkan kekeliruan yang diidap oleh interpretasi konsensus itu lantaran bertentangan dengan realitas. Hal yang sesungguhnya terjadi adalah keterputusan epistemologi (epistemological breaking) antara filsuf Muslim Timur dan Barat yang menandai telah terjadinya pergeseran paradigma (shift of paradigm) dalam ranah pemikiran Islam. Keterputusan epistemologi itu terjadi dalam tiga klasifikasi; pertama, episteme bayani atau sistem pengetahuan indikasional, kedua, episteme irfani atau sistem pengetahuan gnostik, dan ketiga, epistem burhani atau sistem pengetahuan demonstratif.4 Hal ini mengindikasikan bahwa warisan intelektual Islam tidaklah sepenuhnya bergelut pada ranah-ranah yang irasional, sebagaimana dikesankan oleh para pemikir Muslim di wilayah Timur, namun juga rasional sebagaimana tercermin dari karya-karya monumental para pemikir Muslim di wilayah Barat. 4 Dua term pertama adalah sistem pengetahuan yang berkembang di Timur (al masyriq), sedangkan term yang terkahir merupakan sistem pengetahuan yang berkembang di wilayah Barat (al maghrib). 131 2. Ibn Rusyd dan Averroisme Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad atau singkatnya disebut Ibn Rusyd lahir di Cordova pada 520 H/1126 M dan wafat di Maroko pada 1198 M. Ibn Rusyd juga dikenal dengan nama Averroes di belahan dunia Barat. Keahliannya mencakup banyak bidang, termasuk kedokteran, hukum, dan merupakan tokoh filsafat yang paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam sejak tahun 700 sampai 1200. Di samping sebagai seorang yang paling otoritatif dalam memberikan komentar atas karya-karya filsuf Yunani Aristoteles, Ibn Rusyd juga seorang filsuf Muslim yang paling menonjol dalam usahanya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat (al-ittishal bain al-hikmah wa al-syari’ah). Sejak kecil Ibn Rusyd telah mempelajari alQur’an, lalu mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikh, dan sastra Arab, kemudian mendalami ilmu matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu kedokteran. Komentar Ibn Rusyd terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul suatu aliran yang dilekatkan kepada namanya; Averroisme. Selain itu, Ibn Rusyd juga banyak mengomentari karya-karya filsuf Muslim pendahulunya, seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajjah, dan al-Ghazali. Komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Karya-karya monumental Ibn Rusyd tak kurang dari 50 judul buku dari berbagai disiplin ilmu; filsafat, kedokteran, politik, fiqh, dan masalah-masalah agama. Namun, sejauh menyangkut peran Ibn Rusyd sebagai model pencerahan dalam memahami hubungan wahyu dan akal adalah tiga bukunya; Fashl al-Maqal, al-Kashf ‘an Manahij al-Adillah dan Tahafut al-Tahafut (ditulis berturut-turut pada 1178, 1179, dan 1180). Ketiga buku ini memuat pandangan kontroversial Ibn Rusyd yang pernah menggemparkan dunia Eropa pada pertengahan abad ke-13.5 5 Kitab Fash al-Maqal fî Ma Bain al-Syari’`ah wa al-Hikmah min al-Ittishal (terjemahan dalam bahasa Indonesia terbitan Pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul Kaitan Filsafat dengan Syariat) yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan. Al-Kasyf ‘an Manahij al-Adillah fî ‘Aqaid al-Millah (Mengungkap berbagai Metode Argumentasi Ideologi Agama-agama) yang menjelasakan secara terinci masalahmasalah keimanan yang dibahas oleh para filsuf dan teolog Islam. Tahafut alTahafut (Kerancauan dalam Kitab Kerancauan karya al-Ghazali) yang kandungan isinya membela kaum filsuf dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al- 132 Istilah “Averroisme” mulai digunakan di Eropa sekitar tahun 1270, atau 72 tahun setelah Ibn Rusyd meninggal dunia. Kata yang digunakan adalah averroistae yang sesungguhnya lebih merupakan bentuk sinisme untuk merujuk para pengikut dan pengagum Ibn Rusyd. Sejak periode itu, Universitas Paris sebagi pusat ilmu pengetahuan yang memiliki gravitasi luar biasa bagi sarjana Eropa banyak mengkaji pemikiran Ibn Rusyd. Roger Bacon, filsuf Inggris, berada di universitas ini sekitar tahun 1240-1248; Albert Agung mengajar antara tahun 1242-1248; Bonaventura dari tahun 1248-1255; dan Thomas Aquinas antara 1252 dan 1259. Sebagian besar para pengajar di universitas ini adalah pengikut paham atau simpatisan Averroisme (AsSyaukani, 2005). Dalam sejarah filsafat Barat, Averroisme juga dikaitkan dengan pemikiran filsafat keagamaan yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Averroisme Yahudi” dan “Averroisme Kristen”. Averroisme Yahudi berkembang pesat di Andalusia. Para pengikut Averroisme Yahudi umumnya memandang Ibn Rusyd sejajar dengan filsuf besar mereka; Musa ben Maymun atau Maimonides (wafat: 1204) dan Abraham ben Ezra (wafat: 1167) yang kebetulan keduanya hidup di Andalusia sezaman dengan Ibn Rusyd. Tokohtokoh penting Averroisme Yahudi adalah Isaac Albalag (akhir abad ke-13) yang menerjemahkkan Maqasid al-Falasifah, karya Imam al-Ghazali, ke dalam bahasa Ibrani; Joseph ibn Caspi (lahir: 1279), Moses Narboni (wafat: 1362), dan Elijah Delmedi (wafat: 1493), pengikut Averroisme Yahudi terakhir. Sementara itu, Averroisme Kristen sebetulnya merupakan istilah yang agak paradoks karena dunia gereja, khususnya pada abad ke-13 dan ke-14, didominasi oleh kecenderungan memusuhi ajaran-ajaran Ibn Rusyd dan Aristoteles. Namun, beberapa tokoh Kristen pada masa-masa akhir Abad Pertengahan, seperti Thomas Aquinas, menggandrungi ajaran Aristoteles. Tidak ada pengantar paling baik ke filsafat Aristoteles kecuali karya-karya Ibn Rusyd. Ghazali dalam bukunya Tahafut al-Falasifah (Kerancauan-Filsafat-filsafat kaum filosof). Buku lainnya yang juga penting dalam bidang hukum Islam/fiqh, adalah Bidayah al-Mujtahid (permulaan bagi Mujtahid). Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rusyd yang mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. 133 Baik Averroisme Yahudi maupun Averroisme Kristen menganggap Ibn Rusyd telah berjasa menyelesaikan persoalan pelik yang selama berabadabad menjadi momok bagi kaum agamawan, yakni bagaimana mendamaikan wahyu dengan akal, filsafat dengan agama, para nabi dengan Aristoteles. Dalam karyanya, Fasl al-Maqal, yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa penting Eropa, Ibn Rusyd menjawab semua persoalan ini dengan lugas. Sejak Ibn Rusyd meninggal, tradisi rasionalisme dalam filsafat Islam mati. Peristiwa itu juga membawa Ibn Rusyd dikenal sebagai filsuf besar terakhir yang dimiliki umat Islam. Setelah itu, memang muncul beberapa filsuf seperti Mir Damad (wafat: 1631), Mulla Sadra (wafat: 1640), dan Mulla Hadi Sabzawari (wafat: 1910) yang kebetulan semuanya orang Iran. Namun, kerangka besar filsafat mereka adalah ’irfani yang lebih dekat dengan tradisi gnostik ketimbang agnostik.6 Di luar Iran dan secara umum di dunia Sunni, tidak ada lagi filsuf tercerahkan yang lahir setelah Ibn Rusyd. Sebagian orang mengandaikan Ibn Taimiyyah (wafat: 1328) sebagai calon, sedangkan yang lainnya menunjuk Fakhruddin al-Razi (wafat: 1209), Nasiruddin al-Tusi (wafat: 1274), bahkan Ibn Arabi (wafat: 1240). Ibn Rusyd dan semangat Averroisme baru mendapat perhatian umat Islam awal abad ke-20. Gerakan Nahdah (kebangkitan) yang bibitbibitnya disemai oleh tokoh-tokoh semacam Rif’at al-Tahtawi (wafat: 1873), Muhammad Abduh (wafat: 1905), dan Qassim Amin (wafat: 1908) di Mesir; kepada Sayyid Ahmad Khan (wafat: 1898) dan Chiragh ‘Ali (wafat: 1895) di India; juga kepada penulis Kristen Arab yang begitu fasih berbicara tentang kemajuan dan pencerahan, seperti Shibli Shumayyil (wafat: 1917), Farah Antun (wafat: 1922), Georgie Zaidan (wafat: 1914), Nicola Haddad (wafat: 1954), dan Salama Musa (wafat: 1958). Setelah lebih dari 700 tahun, Ibn Rusyd diabaikan, gerakan “Averroisme Arab” abad ke-20 membuktikan bahwa sebuah penantian yang panjang telah hadir kembali. Ibn Rusyd bisa diterima oleh bangsanya sendiri (As-Syaukani, 2005). 6 Gnostik di sini harus dibaca sebagai tradisi nonrasional-bukan irasional-yang lebih mengandalkan refleksi intuitif ketimbang nalar burhani sebagaimana yang digunakan Ibn Rusyd, sementara agnostik harus dipahami sebagai tradisi rasional dan bukan ateis sebagaimana selama ini disalahpahami. Secara harfiah agnostik berarti “ragu-ragu” atau “tidak yakin”. Filsafat dibangun berdasarkan keraguraguan dan ketidakyakinan. 134 3. Ibn Taimiyyah Dan Metode Penafsiran Wahyu Ibn Taimiyyah adalah pemikir Muslim yang produktif. Ia menulis mengenai hampir setiap aspek dalam Islam. Wajdi (tt: 231) memperkirakan bahwa karya Ibn Taimiyyah mencapai 500 buah. Sementara itu, Khan (1983: 315) telah membuat daftar karya tulis Ibn Taimiyyah, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum, yang telah ditemukan bukti fisiknya maupun yang belum, semuanya berjumlah 295 judul. Sebagian dari karya-karya Ibn Taimiyyah merupakan reaksi terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dialami masyarakat muslim pada masanya. Pesan utama yang disampaikannya adalah seruan untuk kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunah. Karya-karya Ibn Taimiyyah dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap kebangkitan gerakan Wahabi pada abad ke-16, dan hampir seluruh gerakan pembaharuan di dunia Islam. Penilaian tersebut menjadi stimulator yang dahsyat kepada para pemikir Muslim. Banyak penulis Muslim seperti Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Mahdi al-Istanbuli, dan Muhammad Khalil Haras telah menulis biografi Ibn Taimiyyah sebagai tokoh pembaru Islam terkemuka.7 Di antara karya tulis yang menyanjung Ibn Taimiyyah antara lain disusun oleh Mar‘i Ibn Yusuf al-Karmi al-Hanbali yang memuat apresiasi beberapa ulama terkemuka seperti Ibn al-Qayyim, al-Dzahabi, Ibn Daqiq, Ibn al-Wardi, dan Abu Hayyan. Tulisan-tulisan ringkas tentang Ibn Taimiyyah dapat ditemukan pula dalam karya H.A.R. Gibb, Fazlur Rahman, Majid Fakhry, dan Nurcholish Madjid. Sementara itu, tulisan Adnan Zarzur, al-Dzahaby, Muhammad Ali al-Shabuny, al-Suyuthy dan al-Zarkasyi mengisyaratkan reputasinya di bidang tafsir atau Ilmu Al-Qur’an. Studi pemikiran Ibn Taimiyyah di bidang tafsir antara lain telah dilakukan oleh al-Julainid yang kajiannya menitikberatkan pada masalah penta’wilan, yakni pengalihan makna ayat dari makna lahiriahnya ke makna lain yang masih tercakup sepanjang pengalihan makna tersebut tidak bertentangan dengan semangat ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah.8 Penta’wilan ayat al-Qur’an dengan cara seperti itu telah banyak dilakukan oleh para filosof 7 Lih. Mar‘i Ibn Yusuf al-Karmi al-Hanbali, 1963, Al-Syahadah al-Zakiyyah fi Tsana’I al-A‘immah ‘ala Ibn Taimiyyah, Beirut: Dar al-Furqan, h. 312 8 Lih. Badruddin al-Zarkasyi, 1957, Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, Mesir: Al-Halaby, h. 221 135 dan para ahli kalam mengenai masalah-masalah ke-tuhanan dan menyangkut masalah ayat-ayat mutasyabihat. Di sini, al-Julainid (1974: 242) memetakan posisi Ibn Taimiyyah dalam konteks perbedaan-perbedaan pandangan tentang penta’wilan al-Qur’an. Hasil yang paling signifikan adalah kritik Ibn Taimiyyah terhadap penta’wilan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, yang dinilainya tidak sejalan dengan cara ulama Salaf dalam memahami alQur’an. Titik berat kajiannya bukan pada metode penafsiran al-Qur’an pada umumnya, tetapi pada metode penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang dipandang perlu penta’wilan. Syafruddin (1994) dalam tesisnya mamaparkan tiga hal yang berkaitan dengan penafsiran Ibn Taimiyyah, yakni pertama, pandangan-pandangan Ibn Taimiyyah tentang ta‘wil, termasuk di dalamnya pembahasan tentang kritik Ibn Taimiyyah atas penta’wilan aliran-aliran pemikiran dalam Islam, baik kalangan filosof, ahli kalam maupun kaum sufi. Kedua, prinsip-prinsip penafsiran Ibn Taimiyyah yang termuat dalam karyanya Muqaddimah fi Uhsul al-Tafsir. Ketiga, tafsir surat al-Ikhlash karya Ibn Tamiyyah sebagai sampel penerapan metode penafsirannya, sekaligus untuk melihat orisinalitas prinsip-prinsip penafsirannya. Dalam tulisan itu, Syafruddin tidak mengemukakan karakteristik penafsiran Ibn Taimiyyah sebagai bagian dari sistem penafsirannya. Lebih dari itu, karya tersebut belum menggambarkan penafsiran Ibn Taimiyyah secara utuh yang termuat dalam empat Juz dari Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah, yang telah dijustifikasi oleh Muhammad al-Sayyid al-Julainid dan diterbitkan ulang dengan judul “Daqaiq al-Tafsir al-Jami’ la Tafsir al-Imam Ibn Taimiyyah” (1966). Paraja (1990: 75) mengungkapkan epistemologi Ibn Taimiyyah yang memuat pandangannya tentang hubungan akal dan wahyu. Menurut Ibn Taimiyyah, akal dan wahyu itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Pendapat akal yang lurus akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar. Akal bukanlah dasar untuk menentukan kebenaran wahyu karena wahyu telah pasti benar dengan sendirinya, baik wahyu itu diketahui oleh akal atau tidak. Wahyu tidak memerlukan pembenaran akal. Wahyu menyempurnakan akal. Akal dan wahyu mungkin bisa bertentangan, tetapi pendapat akal yang jelas akan sesuai dengan wahyu yang benar. Wahyu selamanya tidak dapat dipisahkan dari akal. 136 Metode penulisan tafsir Ibn Taimiyyah adalah tahlili karena ia menyoroti ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur’an Mushaf ‘Utsmani. Dilihat dari bentuk tinjauan dan kandungan informasinya, tahlili menggunakan metode al-tafsir bi al-ma’tsur (Shihab, dkk, 2000: 172-174). Tafsir dengan metode ini menggunakan prinsip penafsiran ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an lain, penafsiran ayat alQur’an dengan pendapat Rasul, penafsiran ayat al-Qur’an dengan pendapat sahabat, dan penafsiran ayat al-Qur’an dengan pendapat Tabi’in (Taimiyyah, tt: h. 46-47). 4. Persoalan Wahyu-Akal Dalam Model Pemikiran Ibn Rusyd Dan Ibn Taimiyyah Seperti telah disinggung pada bagian pengantar di atas, dalam tradisi filsafat Islam, persoalan hubungan antara wahyu dan akal merupakan issu yang selalu hangat diperdebatkan. Issu ini menjadi penting karena memiliki kaitan dengan argumentasi-argumentasi para mutakallimun dan filosof dalam pembahasan tentang konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep etika dan lain sebagainya.9 Para mutakallimun dan filosof itu berorientasi pada usaha untuk membuktikan kesesuaian atau hubungan antara akal dan wahyu.10 Dalam konteks ini konsep akal, wahyu dan ta’wil menjadi topik yang penting. Filosof Muslim terpenting yang berusaha membuktikan hubungan antara akal dan wahyu adalah Ibn Rusyd dengan karyanya “Fasl al-Maqal” dan Ibn Taimiyyah penulis buku “Dar’ Ta’arud al-‘aql wa al-naql” yang sebelumnya diberi judul “Muwafaqat sarih al-ma’qul ‘ala sahih al-manqul”. Yang pertama mencoba menjelaskan “hubungan” sedang yang kedua berusaha menghindarkan pertentangan atau menjelaskan “kesesuaian”. Akan tetapi Arberry (1957) menganggap karya Ibn Rusyd itu sebagai percobaan terakhir untuk membuktikan hubungan antara akal dan wahyu, sedangkan Ibn Taimiyyah digambarkan sebagai orang yang menghentikan 9 Lih. George F. Hourani, 1985, Reason and Tradition in Islamic Ethic, Cambridge: Cambridge University Press, h. 12 10 Lih. A.J. Arberry, 1957, Revelation and Reason in Islam, London: Allen & Unwin, hal. 25 137 percobaan ini. Sejatinya keduanya berasumsi sama bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, tapi karena situasi sosial dan latar belakang pemikiran mereka, kesimpulan yang mereka hasilkan berbeda. Ibn Rusyd tidak saja dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa sains dan filsafat bertentangan dengan agama tapi juga oleh konflik-konflik yang terjadi antara ahli-ahli filsafat dan ilmu agama. Berbeda dari Ibn Rusyd, perhatian Ibn Taimiyyah difokuskan pada pemahaman masyarakat tentang Islam yang dalam pandangannya telah dirusak oleh doktrin-doktrin sufism, teologi dan filsafat seperti yang nampak dalam amalan-amalan bid’ah di masyarakat.11 Dalam membahas masalah wahyu dan akal, Ibn Rusyd menggunakan prinsip hubungan (ittishal) yang dalam argumentasi -argumentasinya mencoba mencari hubungan antara agama dan falsafah. Argumentasi-argumentasinya adalah; pertama, menentukan kedudukan hukum daripada belajar falsafah. Menurutnya belajar falsafah adalah belajar ilmu tentang Tuhan, yaitu kegiatan filsosofis yang mengkaji dan memikirkan segala sesuatu yang wujud (al-mawjudat) yang merupakan pertanda adanya Pencipta, karena al-mawjudat adalah produk dari ciptaan. Lebih sempurna ilmu manusia tentang hasil ciptaan Tuhan (al-mawjudat) lebih sempurna pula ilmu manusia tentang Tuhan. Karena wahyu (syar’i) menggalakkan aktivitas bertafakkur tentang al-mawjudat ini, maka belajar falsafah diwajibkan dan diperintahkan oleh wahyu. Kedua, membuat justifikasi bahwa kebenaran yang diperolehi dari demonstrasi (al-burhan) sesuai dengan kebenaran yang diperoleh dari wahyu. Di sini Ibn Rusyd berargumentasi bahwa di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal (nadzar) untuk memahami segala yang wujud. Karena nadzar ini tidak lain dari proses berpikir yang menggunakan metode logika analogi (qiyas al-‘aqli), maka metode yang terbaik adalah metode demonstrasi (qiyas al-burhani). Sama seperti qiyas dalam ilmu Fiqh (qiyas al-fiqhi), yang digunakan untuk menyimpulkan ketentuan hukum, metode demonstrasi (qiyas al-burhan) digunakan untuk mamahami segala 11 Lih. Isya A. Bello, 1989, Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy, Leiden: E.J.Brill, h. 19 138 yang wujud (al-mawjudat). Hasil dari proses berpikir demonstratif ini adalah kebenaran dan tidak dapat bertentangan dengan kebenaran wahyu, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Kedua tesis di atas merupakan asas bagi kesimpulan Ibn Rusyd selanjutnya yang menyatakan bahwa para filosof memiliki otoritas untuk menta’wilkan al-Qur’an. Tesis di atas masih menyimpan satu pertanyaan; adakah kebenaran yang diperoleh akal tidak akan bercanggah dengan kebenaran wahyu? Jawaban pertanyaan ini tidak dinyatakan secara jelas, akan tetapi dapat dipahami dari teori Ibn Rusyd mengenai kemampuan akal dalam memahami wahyu, dan tentang wahyu yang diklassifikasikan ke dalam makna. Berdasarkan pada kemampuan akal manusia, Ibn Rusyd membahagi masyarakat ke dalam tiga kelompok; pertama; kelompok yang tidak dapat menafsirkan al-Qur’an, kedua; kelompok yang memiliki kemampuan menafsirkan secara dialektik, dan ketiga; kelompok yang mampu menafsirkan secara demonstratif yang disebut ahl al-burhan.12 Akal dalam klassifikasi ini dipahami sebagai kemampuan untuk berpikir dan memahami. Sedangkan wahyu dibagi ke dalam tiga bentuk makna yang terkandung di dalamnya yaitu; 1) teks yang maknanya dapat dipahami dengan tiga metode yang berbeda (metode retorik, dialektik dan demonstratif); 2) teks yang maknanya hanya dapat diketahui dengan metode demonstrasi. Makna yang terkandung dalam teks ini terdiri dari; a) makna dzahir, yaitu teks yang mengandung simbolsimbol (amtsal) yang dibuat untuk menerangkan idea-idea yang dimaksud; b) makna batin yaitu teks yang mengandung ide-ide itu sendiri dan hanya dapat dipahami oleh yang disebut ahl al-burhan; 3) teks yang bersifat ambigu antara dzahir dan batin. Klassifikasi teks wahyu tersebut juga merujuk kepada kemungkinan untuk dapat dipahami dengan akal. Nampaknya, yang dimaksud Ibn Rusyd sebagai hubungan (ittishal) adalah hubungan antara ayat-ayat yang mengandung makna batin dan kemampuan akal untuk memahami dengan metode demonstratif. Oleh karena itu, menurutnya perkataan al-rasikhun fi al-ilm (al Qur’an; 3:7) adalah mereka yang memiliki pengetahuan berdasarkan metode demonstrasi, yaitu para filosof. 12 Lih. George F. Hourani, 1976, Averoes On the Harmony of Religion and Philosophy, London: Luzac & Co, h. 65 139 Dari klassifikasi di atas agaknya jawaban yang diberikan Ibn Rusyd jelas bahwa pertentangan antara akal dan wahyu tidak terjadi apabila akal dipahami sebagai al-burhan. Namun demikian, Ibn Rusyd tetap mengakui adanya kemungkinan pertentangan antara ahl al-burhan dan teks wahyu. Solusi yang terbaik menurutnya adalah seperti cara pengambilan hukum Fiqh. Dalam kes tertentu pengetahuan tentang al-mawjud “tidak disebutkan” dalam wahyu dan dalam teks yang lain “disebutkan”. Jika tidak disebutkan maka harus disimpulkan darinya seperti qiyas dalam Fiqh. Jika pengetahuan itu disebutkan dan makna dzahirnya betentangan dengan hasil pemikiran demonstratif maka diselesaikan dengan dua cara; pertama; dengan interpretasi secara majazi (alegorik) atau kiasan makna dzahir itu sesuai dengan aturan-aturan bahasa Arab yang berlaku, yaitu “menerjemahkan arti suatu ekspresi dari yang bersifat metaforikal kepada pengertian yang sesungguhnya”, kedua; dengan mencari semua makna dzahir dalam al-Qur’an yang bersesuaian dengan interpretasi alegorik atau yang mendekati makna alegorik itu. Akan tetapi untuk menta’wilkan secara majazi makna ayat dzahir pada alternatif pertama Ibn Rusyd tidak hanya bersandar pada aturan-aturan Bahasa Arab saja, tetapi juga menetapkan aturan berdasarkan pada kejelasan simbol dan benda yang disimbolkan untuk menentukan apakah sesuatu ayat dzahir boleh dita’wilkan atau tidak. Jika makna dzahir sesuatu ayat adalah seperti arti yang dimaksudkan (alma’na al-mawjud fi nafsihi), ayat itu tidak perlu dita’wilkan. Jika dzahir ayatayat itu adalah simbol-simbol belaka dan bukan arti yang sesungguhnya dari dzahirnya ayat-ayat itu harus dita’wilkan sesuai dengan kesesuaian antara simbol (al-mitsal) dengan benda yang disimbolkan (al-mumatstsal). Jika simbol dan benda yang disimbolkan dapat mudah diketahui maka setiap orang boleh menta’wilkannya. Tapi jika simbol dan benda yang disimbolkan sulit diketahui atau jika simbol-simbol itu mudah diketahui tapi benda yang disimbolkan sulit untuk diketahui atau jika benda yang disimbulkan dapat dipahami dengan mudah tapi simbol-simbol ayat itu tidak dapat begitu saja diketahui, maka ayat-ayat ini hanya boleh dita’wilkan oleh yang berilmu dan tidak boleh diungkapkan kepada orang awam kecuali dengan penjelasan yang berbeda. 140 Ibn Rusyd tidak menjelaskan lebih jauh tentang standar pengetahuan al-mitsal dan al-mumatstsal atau kriteria untuk membenarkan kebenaran pengetahuan tentang kedua hal itu. Nampaknya asas yang digunakan Ibn Rusyd dalam ta’wil adalah Bahasa Arab yang merujuk kepada kebiasaan (adat lisan al-‘Arab) dan kejelasan simbol serta benda yang disimbolkan, terutama adalah kemampuan akal memahami maknanya dengan menggunakan metode demonstratif. Akan tetapi standar bahasa Arab dengan simbol-simbol itu tidak dikaitkan dengan bahasa sebagai simbol suatu konsep yang dijelaskan Nabi dan dipahami oleh para sahabat dan tabi’in. Demikian pula proses ta’wil yang dijelaskan seakan-akan menggambarkan bahwa pengetahuan ahl al-burhan adalah taken for granted itu benar. Ini bermakna bahwa kebenaran wahyu perlu dikaji ulang dan tidak memberikan ruang untuk menjelaskan proses bagaimana seharusnya pengetahuan demonstrasi dikaji ulang. Pandangan tersebut dapat dipahami sebagai mendahulukan akal daripada wahyu, yaitu pandangan yang bertentangan dengan pemikiran salaf, seperti al-Ghazali, Ibn Hazm, Ibn Taimiyyah atau lainnya. Dengan membatasi makna perkataan al-rasikhun fi al-ilm berarti Ibn Rusyd memberikan otoritas menta’wilkan makna batin al-Qur’an kepada filosof, tanpa mempertimbangkan otoritas Nabi dan para sahabat. Hal ini membahayakan kemutlakan kebenaran wahyu. Demikian pula, pengetahuan para filosof tentang realitas (wujud), yang diperoleh dari metode demonstrasi belum dapat dikatakan final. Dalam masalah doktrin ketuhanan atau konsep tentang Tuhan, misalnya, filsafat Yunani masih mengandung pertentangan dan berbeda dari konsep dalam alQur’an. Jika Ibn Rusyd membahas lebih detail konsep akal tanpa membatasi pada metode demonstrasi filsafat Yunani, maka kesesuaian akal dan wahyu dapat dipahami lebih jelas. Dalam konteks kesesuaian wahyu dan akal itulah, model pemikiran Ibn Taimiyyah relevan untuk disandingkan dengannya. Prinsip “kesesuaian” Ibn Taimiyyah yang berarti tanpa pertentangan tercemin dari judul kitabnya yang menggunakan perkataan muwafaqat dan dar’ ta’arud. Meskipun implikasi makna perkataan ini hampir sama dengan perkataan “ittishal” dalam pandangan Ibn Rusyd, tapi prinsip-prinsip yang digunakan berbeda, terutama dalam memahami makna akal (’aql ) dan dalam menjabarkan wahyu (al-naql, al-sam’i). Prinsip-prinsip Ibn Taimiyyah ini dapat dipahami secara lebih jelas 141 dari komentar dan jawabannya terhadap masalah yang dibahas oleh filosof dan mutakallimun khususnya Fakhr al-Din al-Razi, yaitu; bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi “pertentangan antara akal dan wahyu”. Dari kesemua pembahasan Ibn Taimiyyah sekurang-kurangnya terdapat tiga prinsip utama yang dimaksud untuk menjawab masalah itu dan membangun prinsip kesesuaian antara akal dan wahyu. Ketiga prinsip itu ialah sebagai berikut; Pertama, bahwa rasional atau tradisional bukanlah sifat yang boleh menentukan sesuatu itu benar atau salah, diterima atau ditolak. Ia hanyalah metode atau jalan untuk mengetahui sesuatu. Jika sesuatu itu berasal dari tradisi (al-sam’i) semestinya ia bersifat rasional, sifat tradisional tidak bertentangan dengan sifat rasional. Syari’ah terkadang bersifat tradisional dan terkadang rasional; bersifat tradisional (sam’iyyan) jika ia menetapkan dan menunjukkan sesuatu, dan bersifat rasional jika ia memperingatkan dan menunjukkan sesuatu hal. Kedua, jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka prioritas diberikan kepada wahyu dan menolak akal. Akal tidak mungkin diberi prioritas karena melalui akal kebenaran wahyu dibuktikan. Jika akal diberi prioritas sedangkan akal itu sendiri boleh berbuat salah, maka ia tidak boleh menjadi alat untuk menentukan kebenaran. Di sinipun wahyu akan dianggap mengandung kesalahan. Prinsip ini masih bersifat umum dan tidak termasuk pertentangan antara pengetahuan tradisional (wahyu) dan rasional (akal). Ketiga, jika pertentangan terjadi antara proposisi akal dan wahyu maka harus dikaji apakah proposisi itu qat’i atau dzanni. Jika kedua-dua proposisi itu qat’i, maka tidak mungkin terjadi pertentangan dan jika kedua proposisi itu dzanni maka dipilih proposisi yang lebih pasti (rajih). Jika proposisi yang dihasilkan akal lebih pasti (qat’i), maka prioritas diberikan kepada proposisi akal daripada proposisi dari pengetahuan wahyu (al-sam’i) dan sebaliknya. Tapi proposisi akal diutamakan bukan karena ia berasal dari akal tapi karena sifat qat’inya itu. Secara umum pandangan Ibn Taimiyyah menolak prinsip akal sebagai asas wahyu dan asas bagi menentukan kebenaran wahyu yang berarti mendahulukan akal daripada wahyu. Alasannya, karena keberadaan wahyu berasal dari Nabi (al-sam’i) dan bukan dari akal. Meskipun kebenaran wahyu 142 dapat diketahui dengan pengetahuan akal, tapi pengetahuan akal tidak dapat menetapkan adanya (tsubut) wahyu. Kebenaran wahyu tidak mungkin bergantung pada pengetahuan yang diperoleh akal, sebab sifat dapat dipahami atau diketahui oleh akal bukanlah sifat lazim (sifah lazimah) sesuatu benda. Seandainya kebenaran wahyu itu tidak diketahui atau dibuktikan oleh akal sekalipun tetap memiliki sifat kebenaran, karena itu semua pengetahuan akal tidak dapai dijadikan sebagai asas bagi wahyu atau dalil bagi kebenarannya. Asas kesahihan wahyu adalah kebenaran Nabi (sidq al-rasul). Mendahulukan akal berarti pada mengutamakan pendapat filosof, mutakallim atau sufi daripada risalah Nabi, dan dapat mengakibatkan bid’ah dan kekufuran. Meskipun demikitan, Ibn Taimiyyah sama sekali tidak merendahkan makna akal jika akal dipahami sebagai; a) watak (gharizah) atau b) pengetahuan yang diperoleh dari akal (al-ma’rifa al-hasila bi-l-‘aql). Sebagai gharizah akal menjadi syarat bagi segala macam ilmu, apakah rasional ataupun irrasional, dan dalam kedudukannya sebagai syarat, akal tidak dapat bertentangan dengan wahyu. Demikian pula sebagai pengetahuan yang diperoleh dari gharizah tadi akal dipahami sebagai pengetahuan akal yang jelas dan pasti kebenarannya (‘aqli qat’i). Pada poin ini Ibn Taimiyyah tidak memberikan penjelasan lebih detail atau contoh tentang apa hakikat pengetahuan akal yang pasti (‘aqli qat’i) itu. Mungkin maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui fitrah, seperti yang ia jelaskan dalam kitabnya “Naqd alMantiq”. Tapi mungkin juga yang dimaksud adalah necessary knowledge, yaitu pengetahuan yang menjamin pengetahuan yang pasti (’ilm al-yaqini) secara lafdzi atau maknawi. Pengetahuan ini dimiliki oleh para sahabat Nabi, dan para pengikut-pengikutnya (tabi‘un dan tabi‘ al-tabi’un), sebab baginya mereka itu adalah sumber ilmu pengetahuan tradisi yang harus dipercayai. Pengertian ‘aqli qat’i merujuk kepada pengetahuan yang bukan berasal dari pemikiran spekulatif atau al-burhan seperti pandangan Ibn Rusyd. Selanjutnya dalam mendahulukan wahyu Ibn Taimiyyah berprinsip bahwa wahyu itu benar dan disampaikan melalui argumentasi-argumentasi tradisional dan rasional, karena itu tidak dapat bertentangan dengan pengetahuan akal yang benar. Pertentangan itu mungkin terjadi karena pengetahuan tentang wahyu yang tidak jelas atau pengetahuan akal yang salah. Pengetahuan wahyu yang benar diperoleh dari proses berpikir yang benar 143 dan pengetahuan terminologi yang sesuai dengan tradisi, dan bukan diluar itu. Maka itu ia membedakan terminologi yang digunakan dalam sunnah dan disepakati oleh ahl al-ijma’ dari terminologi yang tidak terdapat dalam tradisi. Untuk membedakan keduanya yang diperlukan adalah pemahaman terhadap tradisi yang merujuk pada perkataan Nabi, Sahabat, tabi‘un and tabi‘ al-tabi’un. Dari mereka inilah otoritas memahami wahyu dalam Islam bermula, sebab Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling tahu kebenaran dan karena itu ia adalah orang paling mampu untuk menerangkan kebenaran. Maka itu ia memahami istilah ta’wil sebagai menjelaskan seperti yang dimaksud Allah atau merujuk kepada apa yang dikehendaki Allah dan kriteria ta’wil yang dapat diterima, yaitu ta’wil yang sesuai dengan arti yang dimaksud oleh “pembicara” atau Tuhan melalui Nabi. Maka dari itu Ibn Taimiyyah tidak membatasi objek ta’wil kepada perkataan majazi dalam al-Qur’an seperti dibahas Ibn Rusyd. Meskipun ia mengartikan ta’wil sebagai penafsiran dan penjelasan ucapan, ia tetap menekankan pada kesesuaiannya dengan makna dzahir dari lafadz ucapan itu. Dalam pandangannya perkataan dzahir yang dapat dipahami dari lafadz bermacam-macam bentuknya, ada yang menurut konteksnya dan ada pula yang dipahami sesuai dengan ikatan-ikatan yang ada di dalamnya. Makna itu tidak memiliki denotasi yang uniform sehingga harus dita’wilkan apa adanya dan tidak memiliki denotasi batin yang harus selalu dipahami secara batin. Jadi perkataan dzahir diketahui dari denotasi lafadz secara mutlak, atau dari denotasi konteksnya atau dari kesamaannya dengan konteks yang lain. Untuk itu Ibn Taimiyyah menetapkan tiga syarat agar ta’wil itu dapat diterima; 1) menjaga agar lafadz itu sesuai dengan makna yang terdapat dalam Bahasa Arab dan maksud al-syari’ serta tidak memahami dengan makna lain; 2) menjaga agar maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembicara dalam konteks lafadznya; 3) memperhatikan ikatan-ikatan yang terdapat dalam lafadz dan yang mengikat maknanya, sebab perbedaan satu lafadz dengan lafadz lain ditentukan oleh ikatan yang menyertainya. Oleh karena itu lafadz-lafadz al-Qur’an tidak boleh dita’wilkan dengan sesuka hati tanpa mengkaji maksud yang sesungguhnya sesuai dengan konteks masing-masing lafadz. Selanjutnya Ibn Taimiyyah membagi ta’wil menjadi dua; pertama, ta’wil yang berkaitan dengan perintah kepada manusia untuk 144 berbuat, disebut dengan al-ta’wil al-talabi, yaitu ta’wil tengang perintah dan larangan (al-amr wa al-nahy). Di sini Ibn Taimiyyah menerima adanya kontradiksi antara satu teks dengan yang lain; kedua, ta’wil yang berkaitan dengan apa-apa yang disampaikan Tuhan (akhbar) tentang diri-Nya, tentang Hari Akhir dan lain-lain yang benar belaka sifatnya. Ta’wil dalam masalah yang kedua hanya Allah saja yang mengetahuinya, sedangkan manusia hanya dapat mengetahui arti literal teks itu, tapi tidak mengetahui ta’wil atau realitas yang sesungguhnya. Dalam masalah-masalah doktrin (akhbar) ini Ibn Taimiyyah tidak melihat adanya kontradiksi teks wahyu seperti dalam al-ta’wil al-talabi, kontradiksi itu muncul hanya dalam akal orang yang memahami. Jelaslah bahwa Ibn Taimiyyah dan Ibn Rusyd berbeda dalam memahami makna ta’wil. Bagi yang pertama ta’wil sama dengan tafsir dan menekankan pada kesesuaian dzahir lafadz dengan makna dan makna dengan maksud al-syari’, sedangkan yang kedua menekankan makna ta’wil pada penjelasan makna sebenarnya (haqiqi) dari makna majazi atau makna batin sesuatu teks. Perbedaan ini dapat dipahami lebih jelas melalui pemahaman mereka dalam menta’wilkan ayat-ayat mutasyabihat yang diterangkan dalam al-Qur’an. Ibn Rusyd memahami bahwa ta’wil ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu berpikir demonstratif, sedangkan bagi Ibn Taimiyyah hanya Allah saja yang tahu karena menurutnya para sahabat dan tabi’un memahami ayat mutasyabihat, tapi mereka tidak mengetahui realitas sesungguhnya (modalitas) dari khabar yang disampaikan Allah itu dan hanya Allah saja yang tahu (la ya’lamu ta’wilahu illallah). Itulah sebabnya mengapa Ibn Taimiyyah tidak menjelaskan perkataan al-rasikhun fi al-ilm, karena ia tidak berkaitan dengan otoritas menta’wilkan. 5. Penutup Usaha Ibn Rusyd untuk menghubungkan akal dan wahyu sangat sistematis, akan tetapi pembatasan makna akal pada kemampuan berpikir demonstratif yang hanya dimiliki oleh filosof mengundang berbagai pertanyaan. Ibn Rusyd tampak seperti berlebihan dalam menilai kemampuan akal dan metode demonstrasi, sementara ia tidak mengamalkan ta’wil yang berasaskan al-burhan dalam membahas issu-issu filsafatnya. 145 Demikian pula apabila Ibnu Rusyd memberikan otoritas kepada filosof untuk menta’wilkan wahyu, melebihi yang lain, ia telah mendahulukan akal daripada wahyu dan ini boleh mengurangi kemutlakan wahyu. Pandangan Ibn Taimiyyah adalah sebaliknya, yaitu memberi prioritas kepada wahyu, namun ia tidak mengesampingkan akal sama sekali. Akal dan pengetahuan akal yang berpikir benar tidak akan bertentangan dengan wahyu. Akal bagi Ibn Taimiyyah tidak memiliki status independent seperti pandangan Ibn Rusyd. Berbeda dari al-Razi, seorang pemikir Muslim terkemuka yang lain, baginya akal tidak dapat menjadi asas bagi wahyu, tapi justru wahyu adalah asas bagi akal. Karena Ibn Taimiyyah tidak mengakui adanya pertentangan antara akal dan wahyu, maka ia melihat itu hanya karena pengetahuan tentang wahyu yang tidak jelas atau pengetahuan akal yang salah. Untuk itu ia memandang perlunya pengetahuan tentang tradisi dan pendekatan linguistik yang benar, dan inilah esensi konsep ta’wil Ibn Taimiyyah. Kebenaran yang diperoleh melalui akal dalam titik tertentu bisa mempunyai kedudukan yang setingkat dengan wahyu. Maka dari itu pintu masuknya bukanlah keimanan yang didasari oleh taqlid buta, tapi kesaksian yang penuh kesadaran (syahadah). Proses kesadaran inilah yang sebetulnya memberikan ruang bagi akal untuk mencapai kebenaran setingkat wahyu. Akal dalam hal ini melalui metode induksi Ibn Rusyd (observasi dan eksperimen), bisa membaca tanda-tanda alam dan menemukan kebenaran di dalamnya. Wahyu (al Qur’an) adalah “inspirasi”, di dalamnya terdapat hukum-hukum dan pengetahuan yang bersifat umum dan pernyataan-pernyataan final. Bagi Ibn Rusyd, dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal (nadzar) untuk memahami segala yang wujud. Karena nadzar tidak lain adalah proses berpikir yang menggunakan metode logika analogi (qiyas al-‘aqli), maka metode yang terbaik adalah metode demonstrasi (qiyas al-burhani). Sama seperti qiyas dalam ilmu Fiqh (qiyas al-fiqhi), yang digunakan untuk menyimpulkan ketentuan hukum, metode demonstrasi (qiyas al-burhan) digunakan untuk mamahami segala yang wujud (al-mawjudat), Hasil dari proses berpikir demonstratif ini adalah kebenaran dan tidak dapat bertentangan dengan kebenaran wahyu, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. 146 Akal secara fitrahnya juga sudah tersetting untuk mendeskripsikan tentang kebenaran. Akal dapat mengetahui perbedaan perbuatan buruk dan baik, cinta dan benci, kebohongan dan kebenaran, yang bathil dan yang haq, dan kata Ibn Taimiyyah “seandainya Allah tidak menurunkan agamanya, manusia dengan akalnya bisa mengetahui hakikat tentang Tuhannya dan kebenaran itu sendiri”. Namun, secara fitrah juga manusia punya kelemahan, lemah dalam menahan nafsu sehingga mudah tertipu daya, suka tergesa-gesa, tidak cermat, dan lain-lain. Maka disinilah urgensi wahyu, sebab manusia tidak hanya perlu mengetahui hakikat kebenaran namun juga perlu ditunjukan jalan atas kebenaran itu sendiri. Wajar jikalau kemudian Ibn Taimiyyah memposisikan akal sebagai instrumen syarat atau watak “gharizah”, hal ini perlu digarisbawahi. Sebab ketika akal difungsikan sebagai gharizah maka ia bisa sejajar dengan wahyu. Gharizah akal akan menjadi syarat bagi segala macam ilmu, apakah rasional ataupun irrasional, dan dalam kedudukannya sebagai syarat, akal tidak dapat bertentangan dengan wahyu. Demikian pula sebagai pengetahuan yang diperoleh dari gharizah tadi akal dipahami sebagai pengetahuan akal yang jelas dan pasti kebenarannya (‘aqli qat’i). Mukhtasar Syamsuddin Dilahirkan di Luwu, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1968, Mukhtasar Syamsuddin saat ini adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Menempuh studi tingkat sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan perhatian khusus pada filsafat timur. Studi lanjut pasca sarjana ditempuh di universitas yang sama dengan spesialisasi pada filsafat agama. Studi tentang filsafat komparatif hingga mendapatkan gelar Ph.D pada bulan Agustus 2006, ditempuh di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan. Sebagai Guru Besar, pengalamannya dalam menekuni bidang spesialisasinya tidak diragukan lagi: pengalaman mengajar, melakukan riset, keterlibatan dalam forum-forum regional-internasional, serta berbagai publikasi karya ilmiah. Mukhtasar dapat dijumpai di [email protected] 147 DAFTAR RUJUKAN Arberry, A. J., 1957, Revelation and Reason in Islam, London: Allen & Unwin Arkoun, Muhammad, 2003, “Rethinking Islam”, dalam Charles Kurzman (ed), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, diterjemahkan oleh Bahrul Ulum, E Kusmadiningrat (peny.), Jakarta: Paramadina, cet. 2 As-Syaukani, Luthfi, 2005, “Sapere Aude!” Ibn Rushd, Kant, dan Proyek Pencerahan Islam, dalam Kompas, Rubrik Bentara: Rabu, 02 Maret 2005 Bello, Iysa A., 1989, Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy, Leiden: E.J.Brill Fakhry, Majid, 1983, A History of Islamic Philosophy, New York: Columbia University Press Gibb, H.A.R., 1978. Modern Trends in Islam, New York: Octagon Books Hanbali, Mar‘i Ibn Yusuf al-Karmi, 1963, Al-Syahadah al-Zakiyyah fi Tsana’I al-A‘immah ‘ala Ibn Taimiyyah, Beirut: Dar al-Furqan Haras, Muhammad Khalil, 1405H, Ba’itsun Nahdhah al-Islamiyyah Ibn Taimiyyah, Tanta: Maktabah al-Shahabah Hourani, George F., 1976, Averoes On the Harmony of Religion and Philosophy, London: Luzac & Co -----------------------, 1985, Reason and Tradition in Islamic Ethic, Cambridge: Cambridge University Press Ibn Rusyd, Abu al-Walid, 1972, Kitab Fash al-Maqal fi Ma Bain al-Syari’ah wa al-Hikmah min al-Ittishal, Mesir: Dar al-Ma’arif Jabiri, Muhammad Abed, al., 2000, Post Tradisionalisme Islam, dikumpulkan dan dialihbahasakan oleh Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS Julainid, Muhammad al-Sayyid, 1974, Al-Imam Ibn Taimiyyah wa Mauqifuhu min Qadhiyyat al-Ta‘wil. Kairo: Al-Hai‘ah al-‘Ammah lisyu‘un alMathabi’ al-Amirah ---------------------(Ed.), tt, Daqaiq al-Tafsir al-Jami’ la Tafsir al-Imam bn Taimiyyah. Damaskus: Mu‘assasah ‘Ulum al-Qur’an 148 Khan, Qamaruddin, 1983, Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Kompas, “Sapere Aude!” Ibn Rushd, Kant, dan Proyek Pencerahan Islam, rubrik Bentara: Rabu, 02 Maret 2005 Madjid, Nurcholish (Ed.), 1984. Khazanah Intelektual Islam, Jakarta: Bulan Bintang Mashud, H., 2008, Pemikiran Ibn Taimiyyah Tentang Metode, Penafsiran Al-Qur’an Sebagai Upaya Pemurnian Pemahaman Terhadap AlQur’an, dalam Jurnal Penelitian Agama, Purwokerto, P3M STAIN Purwokerto, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2000 Paraja, Juhaya S., 1990, “Epistemologi Ibn Taimiyyah”, dalam Jurnal ‘Ulumul Qur’an, No. 7. Th. II, 1990 Shihab, M. Quraish, 1992, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan ------------------------,1994, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Bandung: Pustaka Hidayah Syafruddin, Didin, 1994, “The Principles of Ibn Taimiyya’s Quranic Interpretation”, dalam Thesis, Institut of Islamic Studies, Mc Gill University Taimiyyah, Ibn, tt, al-Tafsir al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah ---------------------, 1971, Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir. Kuwait: Dar alQur’an al-Karim Tim Penyusun, 1994, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, Jilid 2 Wajdi, Muhammad Farid, tt, Dairah al-Ma’arif al-Islamiyyah, Damaskus: Dar al-Ma’rifahli al-Tiba’ah Zarkasyi, Badruddin, 1957, Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, Mesir: Al-Halaby 149 PENDIDIKAN MANUSIA-MANUSIA DEMOKRATIS FILSAFAT PENDIDIKAN NOAM CHOMSKY RELEVANSI SERTA KETERBATASANNYA PADA KONTEKS INDONESIA Reza A.A Wattimena Abstract Education is the backbone of a civilized society. In the democratic society, education plays an important role to create, spread, and maintain the democratic ideals. That is the main idea in Noam Chomsky’s philosophy of education. There is a deep connection between democratic principles on the one hand, and democratic education paradigm on the other hand. However, these ideal is threatened by authoritarian way of thinking that exist in totalitarian ideology and capitalistic way of thinking. These two ideologies repress human freedom, and destroy democratic culture which is the bed rock of democratic society. Chomsky offers us a knowledge concerning the way to redesign education in facing the challenges of democratic society. Key words Education. Freedom. Democracy. Equality. Totalitarism. Capitalism. Abstrak Pendidikan adalah tulang punggung dari masyarakat yang beradab. Di dalam masyarakat demokratis, pendidikan memainkan peranan penting untuk menciptakan, menyebarkan, dan merawat prinsip-prinsip ideal demokrasi. Inilah argumen utama dari filsafat pendidikan Noam Chomsky. Ada hubungan yang amat erat antara prinsip-prinsip demokratis di satu sisi, dan paradigma pendidikan demokratis di sisi lain. Akan tetapi, nilai-nilai demokratis ini sekarang diancam oleh cara berpikir otoriter yang ada di dalam ideologi-ideologi totaliter dan cara berpikir kapitalistik. Dua bentuk ideologi ini menindas kebebasan manusia, dan menghancurkan kultur demokratis yang menjadi dasar dari masyarakat demokratis. Chomsky menawarkan 150 pengetahuan tentang cara untuk menata ulang pendidikan untuk menanggapi tantangan-tantangan di dalam masyarakat demokratis. Kata kunci Pendidikan. Kebebasan. Demokrasi. Kesetaraan. Totalitarisme. Kapitalisme 1. Pengantar Sebagaimana dinyatakan oleh Dan Satriana dari Lembaga Advokasi Pendidikan dalam diskusi di ITB, Bandung pada 2011 lalu, pendidikan Indonesia dipenuhi oleh masalah pada tiga level.1 Level pertama adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Level kedua adalah pendidikan yang tidak bisa secara universal diakses oleh setiap warga negara Indonesia. Dan level ketiga adalah kurikulum pendidikan yang tidak menggunakan paradigma pendidikan yang tepat. “Liberalisasi pendidikan di Indonesia”, demikian katanya dalam diskusi tersebut, “jauh melebihi negara-negara yang mengaku menganut sistem liberal sekalipun. Liberalisasi ini akan membuat Anda dicetak sebagai pekerja tanpa peduli apa potensi Anda sebenarnya.”2 Di dalam proses itu, soal-soal yang amat penting, seperti pendidikan karakter dan pendidikan nilai, justru sama sekali diabaikan. Di sisi lain, dalam diskusi yang sama, Ramadhani Pratama Guna dari Majalah Ganesha- Kelompok Studi Sejarah, Ekonomi, dan Politik memiliki pendapat yang berbeda.3 Baginya beragam masalah pendidikan muncul, karena kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah di bidang pendidikan nasional itu sendiri, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Kesalahan kebijakan itu berbuah pada krisis di tiga level pendidikan, sebagaimana dituliskan sebelumnya, yakni minimnya sarana dan prasarana pendidikan di berbagai tempat di Indonesia, sulitnya akses pendidikan, dan kesalahan paradigma pendidikan di dalam membuat kurikulum pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. 1 http://www.itb.ac.id/news/3441.xhtml pada 2 April 2012, 15.00. Saya juga mendapatkan hal serupa dari pengamatan saya terhadap situasi pendidikan di Indonesia. 2Ibid. 3Ibid. 151 Pada hemat saya, kedua argumen tersebut sejalan dengan argumen Chomsky, bahwa dunia pendidikan kita ditawan oleh pola berpikir otoriter yang kini tersebar begitu luas di masyarakat kita, dan juga masyarakat dunia. Saya akan mencoba menjelaskan argumen Chomsky tersebut, menunjukkan kaitannya dengan situasi Indonesia, dan memberikan catatan kritis atasnya. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Awalnya, saya akan menjelaskan riwayat hidup dan pemikiran Noam Chomsky (1). Pada bagian ini, saya banyak terbantu dari uraian Christian Garland. Lalu, saya akan menjelaskan pokok-pokok argumen Chomsky tentang pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan kultur masyarakat demokratis (2). Saya akan membaca tulisan Chomsky langsung yang ditulisnya bersama dengan Donaldo Macedo. Seluruh tulisan ini akan saya tutup dengan menunjukkan relevansi pemikiran Chomsky, keterbatasan pemikirannya dalam konteks Indonesia, dan catatan kritis untuk mengembangkan argumennya. (3) 2. Noam Chomsky, Hidup dan Karyanya Noam Chomsky (1928-...) dikenal sebagai seorang filsuf politik, sekaligus aktivis sosial politik di Amerika Serikat.4 Saat ini, ia berkarya sebagai professor linguistik di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Walaupun seorang ahli linguistik, filsafat bahasa, Chomsky kini justru menjadi seorang intelektual publik yang paling tajam melakukan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. Jadi, di satu sisi, ia adalah seorang ahli bahasa. Namun, di sisi lain, ia adalah seorang tokoh politis yang berpengaruh besar di Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Pada hemat saya, ini adalah perpaduan yang amat unik, dan amat jarang ditemukan.5 Chomsky, sebagaimana ditulis oleh Garland, juga adalah 4 Saya terinspirasi dari http://www.chomsky.info/bios/2009----.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), Ini adalah tulisan Garland, Christian, International Encyclopedia of Revolution and Protest, Immanuel Ness, ed., Blackwell Publishing, 2009. 5 Tradisi filsafat yang mengaitkan dirinya secara langsung dengan kehidupan politik praktis sebenarnya bukanlah hal baru. Di dalam sejarah filsafat, kita bisa melihat bagaimana Sokrates, Plato, Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Martin Heidegger, Bertrand Russell, John Dewey, Jean-Paul Sartre, dan Juergen Habermas secara aktif mengaitkan pemikiran mereka dengan situasi politik yang ada. Pada hemat saya, Noam Chomsky dapat disejajarkan dengan nama-nama besar tersebut. 152 seorang kritikus yang amat tajam atas berbagai upaya Amerika Serikat untuk menguasai (baca=hegemoni) dunia, serta agenda-agenda politik ekonomi neoliberalisme yang disebarkannya. Ia menegaskan, bahwa ideologi dan motivasi dominatif tersebut akan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kelas berpunya (minoritas) dan kelas yang tak berpunya (mayoritas).6 Kritik Chomsky bukanlah sebuah kritik kosong. Setelah 2008 lalu, kritiknya terbukti, dan Amerika Serikat memasuki masa resesi (sampai 2012 sewaktu tulisan ini dibuat) yang belum jelas kapan dan bagaimana berakhirnya.7 Di sisi lain, ia juga amat tajam melakukan kritik terhadap media massa-media massa raksasa di Amerika Serikat, terutama karena mereka sering memberitakan hal-hal tertentu yang menciptakan “opini publik yang direkayasa” (manufactured public opinion) untuk membenarkan kepentingan-kepentingan sistem ekonomi pasar bebas kapitalisme, dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut.8 Sebagaimana dicatat oleh Garland, sudah lebih dari lima puluh tahun, Chomsky mengritik dengan keras semua aksi militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Di sisi lain, ia juga amat membenci sikap munafik Amerika Serikat, terutama terkait dengan dukungannya terhadap rezim-rezim totaliter di seluruh dunia, sikap kejamnya pada gerakan-gerakan demokratis di seluruh dunia, yang notabene bertentangan dengan filosofi dasar negara itu, yakni demokrasi dan kebebasan. Intinya, bagi Chomsky, apa yang dikatakan oleh 6 Kritik paling tajam dari pemikir-pemikir yang kritis terhadap globalisasi adalah, bahwa globalisasi adalah proses yang hanya menguntungkan segelintir pihak bermodal, dan dengan itu mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih luas, seperti kepentingan mayoritas, maupun kepentingan alam. Jadi, esensi globalisasi sebenarnya adalah ketidakadilan. 7 Resesi dimulai dengan bangkrutnya Lehmann Brothers di Amerika Serikat, dan kacaunya harga serta bunga kredit rumah di Amerika Serikat. Resesi ini dimulai di Amerika Serikat, dan dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia, mulai dari tidak terkendalinya hutang luar negeri di berbagai negara, sampai dengan kenaikan harga minyak yang juga tak terkendali. Kini, Maret 2012, Uni Eropa juga sedang mengalami masalah finansial terkait dengan hutang luar negeri, dan kesalahan tata kelola keuangan negara. 8 http://www.chomsky.info/bios/2009----.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “Chomsky is also an incisive critic of the ideological role of the mainstream corporate mass media, which, he maintains, “manufactures consent” toward the desirability of capitalism and the political powers supportive of it.” 153 Amerika Serikat berkebalikan dengan apa yang dilakukannya di kenyataan.9 Secara faktual telah terbukti, bahwa Amerika Serikat berdiri di belakang berbagai rezim totaliter yang berkuasa di berbagai belahan dunia, terutama Amerika Selatan, Timur Tengah, dan di Asia.10 Tentang ini semua, Chomsky menulis begini, “Sebagai negara yang paling kuat, AS membuat aturannya sendiri, menggunakan kekuatan dan menerapkan perang ekonomi seturut kehendaknya.”11 Dalam beberapa kasus, sebagaimana dicatat oleh Garland, AS memberikan sanksi pada negara-negara yang tidak mau turut dalam menerapkan ideologi pasar bebasnya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Chomsky juga amat tajam mengritik media massa-media massa besar di AS. Baginya, sebagaimana dicatat oleh Garland, media massa di AS menggunakan model propaganda (propaganda model) di dalam pemberitaan, sehingga justru memperkuat dominasi pihak-pihak yang sudah berkuasa, baik berkuasa secara modal maupun politik. Dengan kata lain, media massa yang ada berpihak pada status quo, dan dengan itu menyingkirkan kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya kritis pada kekuasaan yang ada.12 Garland juga mencatat, bahwa dalam 9 Ibid, “Over the past five decades, Chomsky has offered a searing critical indictment of US foreign policy and its many military interventions across the globe, pointing out that the US‘s continued support for undemocratic regimes, and hostility to popular or democratic movements, is at odds with its professed claim to be spreading democracy and freedom and support for tendencies aiming toward that end.” 10 Beberapa penelitian berhasil membuktikan, bahwa AS berada di balik jatuhnya Soekarno di Indonesia, sekaligus naik dan berkuasanya rezim Orde Baru di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Untuk keterangan lebih jauh, anda bisa lihat di Wardaya, Baskara, Bung Karno Menggugat, Galang Press, Yogyakarta, 2009. 11 http://www.chomsky.info/bios/2009----.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “As the most powerful state, the US makes its own laws, using force and conducting economic warfare at will.” It also threatens sanctions against countries that do not abide by its conveniently flexible notions of “free trade.“ 12 Bukan hanya media massa, tetapi kaum intelektual, termasuk yang berada di universitas, juga seringkali menulis dan berkarya untuk memberikan pembenaran pada sistem kekuasaan yang ada. Ada yang melakukannya secara sadar, dan ada yang tidak sadar. Pendalaman bisa dilihat di Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan di Negara Orde Baru, Gramedia, Jakarta, 1993. Ulasan yang juga tajam tentang ini juga dapat dilihat dalam Kelly, Mark G.E., The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge, London, 2009. 154 ranah paham-paham politik, Chomsky bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir anarkis-libertarian yang ide utamanya adalah kebebasan (freedom). Otomatis, ia banyak membaca tulisan para pemikir Marxis sekaligus para pemikir liberalisme, dan semua itu mempengaruhi posisi epistemologis, etis, maupun politisnya. Perjuangan politis Chomsky menggunakan prinsip “kemenangan-kemenangan jangka pendek” (short term victories). Artinya, kita tidak hanya perlu untuk membangun strategi perubahan jangka panjang semata, tetapi juga mampu membuat perubahan-perubahan kecil dalam jangka pendek yang bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama mereka yang tertindas.13 3. Demokrasi dan Pendidikan Berbicara tentang hubungan antara demokrasi (democracy) dan pendidikan (education), mau tidak mau, seperti ditegaskan oleh Chomsky, kita akan berjumpa dengan pemikiran salah satu filsuf besar Amerika Serikat di abad kedua puluh, yakni John Dewey.14 Chomsky sendiri mengakui, bahwa pemikiran Dewey tentang pendidikan juga mempengaruhi pemikirannya. Salah satu argumen yang cukup menarik, yang diajukan oleh Dewey adalah, bahwa reformasi pendidikan (reform in education), atau perubahan paradigma pendidikan, perlu dilakukan sejak orang masih berusia muda. Dalam konteks ini, tetaplah perlu diperhatikan, bahwa menurut Dewey, tujuan pendidikan bukanlah menghasilkan barang-barang bagus yang bisa dijual dan menambah kas negara, melainkan menghasilkan manusia-manusia bebas (produces free men) yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi yang setara (equal relation).15 Itulah tujuan pendidikan yang sejati, yang sekarang ini banyak terlupakan.16 13 http://www.chomsky.info/bios/2009----.htm (7 Maret 2012 jam 17.00), “Chomsky‘s position on achieving small victories in the short term which “expand the floor of the cage“ 14 Bagian ini diinspirasikan langsung dari tulisan Chomsky, Noam, Democracy and Mis-Education, Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2005, hal. 37. 15 Seperti dikutip oleh Chomsky, ibid. 16 Terkait dengan tema tulisan ini, yakni demokrasi dan pendidikan, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh John Dewey, dan juga oleh Chomsky, ini amat cocok untuk mendorong terciptanya manusia-manusia demokratis yang mampu 155 Pada masa Dewey hidup, dan juga, pada hemat saya, sekarang ini, pendidikan sedang diancam oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan dari rezim-rezim otoriter (authoritarian regimes) yang ingin menciptakan manusia-manusia yang tunduk dan patuh (docile human) pada ideologi yang ada. Sementara yang kedua adalah kekuatan dari sistem kapitalisme yang hendak mengubah konsep warga negara (citizenship) yang bebas menjadi konsep konsumen (consumer) yang bebas, yang pikirannya hanya terfokus pada konsumsi tanpa batas semata. Dua kekuatan ini, pada hemat saya, masih dapat kita temukan sekarang ini. Rezim otoriter sekarang ini banyak mengatasnamakan agama dan tradisi untuk melenyapkan kebebasan manusia. Sementara sistem kapitalisme, dengan daya pikat konsumtivismenya, masih mencengkram pikiran banyak orang, sehingga mereka kehilangan kesadarannya sebagai warga negara, dan hanya semata sibuk mengumpulkan uang, serta membeli lebih banyak barang (consumo ergo sum= aku membeli maka aku ada).17 Dua kekuatan ini bersikap menindas pada kebebasan sejati manusia, yang merupakan tujuan dasar pendidikan. Yang harus diperhatikan adalah, bahwa Dewey dan Chomsky adalah pemikir-pemikir besar dunia yang memiliki akar kuat pada pemikiran Marxisme (marxism) sekaligus liberalisme klasik (classical liberalism).18 Walaupun terlihat berbeda, dua aliran berpikir tersebut amat menekankan kebebasan manusia di hadapan masyarakat dan alam. Sistem kapitalisme secara maksimal mengembangkan keadilan dan kemakmuran untuk semua di dalam masyarakat demokratis. Argumen sebaliknya, menurut saya, juga benar, bahwa pola pendidikan yang bertentangan dengan paradigma pendidikan ini justru bisa menciptakan manusia-manusia anti demokrasi, yang, pada akhirnya, justru bisa merusak proses-proses demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi tak terjadi, maka jalan untuk sampai pada keadilan, kemakmuran, serta kebebasan diri untuk semua akan semakin kelam. 17 Slogan baru kapitalisme abad 21, di mana kualitas diri seseorang dinilai dari sejauh mana ia mampu membeli barang di dalam hidupnya, walaupun ia tak lagi membutuhkannya. Pola berpikir ini menumpulkan solidaritas dan kritik sosial yang sesungguhnya adalah komponen penting di dalam masyarakat demokratis. Dalam arti ini, dapatlah dikatakan, menurut saya, bahwa kapitalisme justru menghancurkan demokrasi, dan menciptakan penderitaan untuk semua. 18Saya juga melihat, bahwa miskinnya perkembangan wacana Marxisme dan sosialisme, yang merupakan peredam gelombang perusak kapitalisme, berkontribusi besar dalam semakin berkembangnya pola pikir kapitalisme yang bercirikan sikap rakus dan penumpukan kekayaan tanpa batas. 156 pasar bebas (free market capitalism) dengan tirani modalnya dan sistem totalitarisme religius (religious totalitarianism) dengan tirani imannya jelas berseberangan amat tajam dengan kedua aliran berpikir tersebut. Totalitarisme religius menginginkan terciptanya manusia-manusia yang tunduk dan patuh pada doktrin-doktrin religius yang seringkali bersifat eksklusif dan tradisional. Sementara kapitalisme pasar bebas mengingkan terciptanya manusia-manusia yang menjadikan uang dan daya beli sebagai satu-satunya ukuran kemanusiaan seseorang. Keduanya menjajah kebebasan, dan keduanya menciptakan penderitaan dalam hidup manusia. Pendidikan di dunia haruslah menyadari pengaruh dua hal tersebut, dan bersikap kritis terhadapnya.19 Chomsky mengajak kita kembali mengingat tujuan utama pendidikan, yakni menghasilkan manusia-manusia yang bebas, yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi dan kondisi yang setara. Maka dapatlah dikatakan, bahwa pendidikan adalah suatu proses produksi, namun bukanlah produksi barang-barang dengan cetakan ketat yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan produksi manusia-manusia bebas. Di sisi lain, Chomsky juga mengutip pendapat Bertrand Russell, seorang filsuf besar asal Inggris di awal abad keduapuluh lalu, tentang pendidikan. Baginya, pendidikan adalah suatu proses untuk memberi makna dari segala sesuatu, dan bukan untuk menguasainya (manusia dan alam). Pendidikan juga adalah proses untuk menciptakan warga negara yang bijak dan masyarakat yang bebas (wise citizens and free society). Dalam arti ini, menurut Russell, sebagaimana dibaca oleh Chomsky, kebijaksanaan publik seorang warga negara mencakup dua hal, yakni kepatuhan pada hukum seorang warga negara pada hukum di satu sisi, dan kreativitas individual dalam berkarya serta mencipta ulang hidupnya di sisi lain. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang dan dinamis.20 Analogi yang diberikan Russell adalah, bagaikan seorang tukang kebun (guru dan masyarakat) merawat tanaman yang indah (siswa dan siswi) yang dilihat sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, dan 19 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ...hal. 38. 20 Seimbang berarti keduanya mendapat tempat. Dinamis berarti perhitungannya bukanlah seimbang matematis (50-50), tetapi bergerak tergantung pada perkembangan konteks kehidupan yang terjadi. 157 memberikannya pupuk yang menyuburkan, air, serta sinar matahari yang menumbuhkan. Inilah yang disebut Chomsky, dengan mengutip Dewey dan Russell, sebagai paradigma humanistik dalam pendidikan (humanistic paradigm in education). Akar dari paradigma ini, menurutnya, adalah tradisi filsafat pencerahan (enlightenment philosophy) yang melihat manusia subyek yang bebas dan berpikir (free and thinking subject). Dalam konteks ini, pendidikan bukanlah seperti mengisi ember dengan air sampai penuh, seperti mengisi kepala peserta didik sampai penuh, melainkan bagaikan menemani sebuah tanaman, sampai ia bisa berkembang sesuai dengan jati diri tanaman tersebut, seperti menemani peserta didik, sehingga ia bisa berkembang sesuai dengan jati dirinya.21 “Dengan kata lain,” demikian tulis Chomsky, “(tujuan pendidikan-Reza) adalah untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan pola-pola kreatif yang normal bisa bertumbuhkembang dengan baik.”22 Dalam bahasa yang lebih lugas, tujuan pendidikan adalah menciptakan situasi yang memadai, sehingga kreativitas bisa bertumbuh di berbagai bidang, terutama dalam diri peserta didik yang notabene adalah anak-anak kita juga.23 Jika sistem pendidikan kita di Indonesia memahami dan memeluk paradigma pendidikan humanistik ini, menerapkannya dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional, serta memastikan pelaksanaannya dengan baik, maka bangsa kita, menurut saya, sejalan dengan pemikiran Chomsky, bisa menciptakan manusia-manusia yang terbebas dari pola pikir menguasai (dominasi) dan mengumpulkan harta serta kuasa semata. Yang ada kemudian, sebagai hasil dari sistem pendidikan humanistik yang (andaikan) telah kita ciptakan, adalah manusia-manusia yang fokus hidupnya adalah menciptakan hubungan-hubungan yang setara antar manusia, kerja sama 21 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ...hal. 38. 22 Ibid. 23 Sejauh saya tafsirkan, dalam bahasa Immanuel Kant, pendidikan adalah upaya untuk membangun “kondisi-kondisi yang memungkinkan” (die Bedingungen der Moeglichkeit) terciptanya kreativitas di segala bidang. Pada hemat saya, filsafat pendidikan Chomsky, Dewey, dan Russell bisa dimasukan ke dalam filsafat transendental pendidikan dengan pola berpikir semacam itu. Tentang filsafat transendental Kantian, anda bisa melihat di Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kritis Immanuel Kant, Evolitera, Jakarta, 2010. Anda juga bisa mendapatkannya di www.rumahfilsafat.com 158 lintas suku, agama, dan ras, mampu dan mau berbagi, serta berpartisipasi untuk menciptakan kebaikan bersama secara demokratis.24 Sekarang ini, di Indonesia, dan di seluruh dunia, pada hemat saya, paradigma pendidikan yang digunakan adalah paradigma dominasi dan kompetisi (competitive and dominating paradigm). Artinya, segala sesuatu harus dilombakan, dan pemenang bisa mendapatkan segalanya, mulai dari uang, kekuasaan, dan, tentu saja, kenikmatan tanpa batas. Dalam bahasa Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Chomsky, yakni pendidikan yang menjadikan manusia sebagai penguasa dari manusia lainnya, yang rakus, serta tidak ingin membagikan apapun untuk siapapun, kecuali itu memberikan keuntungan pada dirinya.25 Sadar atau tidak, pola berpikir inilah yang kita kembangkan di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia, dan kita tanamkan secara sistematik serta represif pada anak-anak kita.26 Chomsky menegaskan, betapa besarnya pertentangan antara paradigma pendidikan humanistik yang dirumuskan oleh Dewey dan Russell, sebagai pewaris filsafat pencerahan, di satu sisi, dan paradigma pendidikan kompetitif dan dominatif yang sekarang ini digunakan di berbagai negara, dan juga, menurut saya, di Indonesia di sisi lain. Bahkan dengan agak sinis, Chomsky menyatakan, bahwa seluruh paradigma dominatif dan kompetitif dalam pendidikan dapat diringkas dalam satu kalimat berikut, yakni pendidikan yang berfokus untuk mencapai prestasi, “memperoleh kekayaan, dan melupakan semua, kecuali dirinya sendiri”.27 Yang menarik, menurut saya, adalah betapa sering argumen ini dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith tentang ekonomi kapitalis dan pasar bebas. Padahal, menurut saya, sejalan dengan Chomsky, jika kita secara langsung membaca dan menekuni 24 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 39. 25 Ibid. 26 Kompetisi dilakukan di berbagai tingkatan pendidikan. Pemenang dianggap lebih baik dari yang kalah. Yang ditonjolkan adalah kompetisi. Kolaborasi hanya dilakukan dengan orang-orang sekelompok. Sementara kelompok lain dianggap musuh. Pola inilah yang, menurut saya, meracuni seluruh sistem pendidikan kita. Untuk lebih jauh, anda bisa melihat tulisan saya dalam Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kata, Evolitera, Jakarta, 2011. Anda juga bisa melihat www. rumahfilsafat.com 27 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ...hal. 39. 159 tulisan-tulisan Adam Smith, terutama pada buku The Moral Sentiment dan The Wealth of Nations, kita akan menemukan, bahwa, menurut Smith, fokus dari aktivitas manusia bukanlah kompetisi dan dominasi, melainkan empati (empathy), kesetaraan antar manusia (human equality), dan pola kerja kreatif sebagai bentuk kerja sama antar manusia (human creativity and cooperation). Dalam hal ini, para pemikir pendukung sistem kapitalisme pasar bebas, menurut saya, bisa dianggap telah memfitnah Adam Smith, seorang pemikir Inggris besar dan bapak ekonomi, untuk membenarkan argumen-argumen mereka yang sebenarnya bengkok.28 Untuk memberi contoh konkret atas gejala ini, Chomsky mengajak kita untuk melihat perkembangan terbaru di Eropa Timur, terutama setelah jatuhnya Uni Soviet sejak 1989 lalu.29 Ia mengutip ungkapan salah seorang pastur Katolik yang dulunya adalah seorang pemrotes keras rezim komunis di Jerman Timur. Dalam salah satu wawancara di New York Times, pastur tersebut berkata begini, “Kompetisi brutal dan nafsu atas uang menghancurkan perasaan kita sebagai satu komunitas, serta hampir semua orang merasakan depresi atau ketidakamanan.”30 Bisa juga dikatakan, bahwa Jerman Timur keluar dari rezim otoriter komunisme, namun kini justru memasuki rezim otoriter yang sama sekali lain, yakni sistem kapitalisme dengan obsesinya pada modal dan penumpukan kuasa tanpa batas, bahkan dengan melindas nilai-nilai kehidupan komunitas maupun kemanusiaan. Dua hal ini jelas amat menghambat proses manusia untuk menjadi manusia-manusia bebas yang mampu berelasi satu sama lain secara setara. 28Di dalam berbagai kuliah maupun tulisannya, B. Herry Priyono, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, telah berulang kali menegaskan argumen ini. Setelah mencoba membaca tulisan-tulisan Adam Smith, saya pun mempunyai kesimpulan yang sama dengan beliau. Silahkan lihat lebih jauh dalam buku Priyono, B. Herry (ed), Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005. 29 Ada beragam pendapat tentang proses-proses demokrasi yang terjadi di bekas negara-negara jajahan Uni Soviet. Dalam salah satu wawancara dengan teman yang berasal dari Polandia, saya menemukan, bahwa sebagian rakyat Polandia puas dengan perkembangan terbaru mereka, yakni keluar dari komunisme dan memasuki sistem demokrasi serta pasar bebas. Namun, di sisi lain, terutama dari sudut pandang orang-orang yang pernah cukup lama hidup di dalam rezim komunis, nada pesimis dan kecewa lebih terasa, akibat sikap rakus-individualis dan kompetisi tidak sehat yang semakin meluas. 30 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 40. 160 Nilai-nilai individualistik yang mengabaikan solidaritas sosial berkembang pesat di berbagai masyarakat dunia sekarang ini. Di satu sisi, orang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Di sisi lain, tingkat kecemasan menjadi amat tinggi, karena tidak ada jaring pengaman yang menangkap mereka, ketika jatuh atau gagal dalam kehidupan.31 Pada titik ini, menurut saya, proses globalisasi yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah proses penyebaran nilai-nilai individualisme khas Amerika Serikat ke seluruh dunia. Di dalam penyebaran nilai-nilai tersebut, solidaritas sosial yang menjadi fondasi dari banyak komunitas, dan juga merupakan fondasi bagi proses-proses demokrasi yang sehat, secara perlahan namun pasti terkikis. Yang juga perlu diperhatikan, terutama dengan melihat situasi dewasa ini, nilai-nilai invidiualisme justru membawa kehancuran pada komunitas, ketidakadilan akibat kesenjangan sosial yang begitu tajam antara si kaya dan si miskin, serta krisis ekonomi raksasa yang merugikan begitu banyak pihak yang tak bersalah. Proses globalisasi (baca= Amerikanisasi) bisa dibayangkan sebagai proses penyebaran “racun” politis ke seluruh dunia.32 Di dalam semua proses tersebut, menurut saya, dunia pendidikan di Indonesia, dan juga seluruh dunia, tidak menjalankan fungsinya sebagai institusi kritis, tetapi justru mengabdi pada pengembangan sekaligus penyebaran nilai-nilai individualistik yang egois dan rakus tersebut. Untuk menjelaskan argumen ini, Chomsky mengutip tulisan David Montgomery, seorang sejarahwan dari Inggris. Menurut Montgomery, Amerika Serikat modern adalah negara yang dibangun dari pemberontakan kelas pekerja terhadap kelas penguasa, mulai dari kelas penguasa dari Inggris, maupun kelas penguasa modal yang rakus dan enggan berbagi.33 Pemberontakan itu berbentuk protes keras dan berkelanjutan dari awal abad kesembilan belas sampai dengan 1950-an. Chomsky sepakat dengan argumen 31 Ibid, hal. 41. 32 Di dalam berbagai tulisannya, Joseph Stiglitz telah mengajukan hal yang sama. Globalisasi dengan kapitalisme pasar bebasnya memberikan keuntungan berlimpah bagi segelintir orang, dan membiarkan orang-orang lainnya mendapatkan sisa-sisa kapital, sehingga mereka hidup dalam kekurangan. Baca Stiglitz, Joseph, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Company, USA, 2002. 33 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 41. 161 ini. Yang melakukan protes ini adalah orang-orang biasa, kaum pekerja, terutama kaum perempuan. Mereka bangkit dan bekerja sama untuk menolak nilai-nilai kelas penguasa borjuis yang individualistik, kompetitif, dan penuh dengan nuansa kerakusan. Mereka memperjuangkan perbaikan untuk nasib mereka yang direndahkan, dan situasi kerja maupun hidup mereka yang tidak manusiawi. Perbudakan memang dihapus. Namun, jenis perbudakan baru lahir, yakni apa yang disebut Chomsky sebagai perbudakan yang bergaji (wage slavery).34 Pada saat yang sama, minat pada karya-karya sastra klasik dan filsafat menurun drastis, terutama di kalangan para pekerja kasar yang hidupnya bagaikan “budak yang bergaji”. Para pejuang kelas pekerja, sebagian dari mereka adalah kaum perempuan, menolak tata kelola politis semacam ini, dan mengorganisir gerakan perubahan (change movement). Gerakan perubahan tersebut berhasil, dan terciptalah Amerika Serikat modern. Masa-masa itu, yakni masa-masa kapitalisme awal di AS, sekitar abad 19, adalah masa-masa yang amat suram bagi kaum pekerja (working class). Mayoritas kelas pekerja hidup di perkebunan maupun industri yang dikuasai oleh keluarga-keluarga yang, sebagaimana dicatat oleh Chomsky, “menerapkan prinsip monarkial di tanah yang demokratis.”35 (monarchic principle in democratic soil) Mereka menindas setiap bentuk kebebasan, martabat manusia, kesehatan, moralitas, dan bahkan intelektualitas yang ada, dan mengubahnya menjadi semata nilai komersial (commercial values) dan penumpukan keuntungan (accumulation of wealth). Pada masa itu, agama pun tak berdaya. Alih-alih melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kekuatan yang menindas martabat manusia, agama justru menjadi legitimasi bagi otoritas yang berkuasa, yang justru melakukan penindasan.36 Chomsky menyebutnya sebagai “para pendeta yang telah dibeli.”37 (bought priesthood) 34 Situasi yang masih dengan mudah kita temukan saat ini di Indonesia. Banyak orang bekerja begitu keras, namun mendapatkan begitu sedikit, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai kaum budak yang bergaji. 35 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 42. 36Saya rasa situasi yang sama, yang mendorong Marx untuk merumuskan argumennya tentang agama sebagai tanda keterasingan manusia. Agama adalah candu bagi rakyat yang tak mampu mengubah realitas hidupnya ke arah yang lebih, dan memilih untuk bersikap pasrah. Lihat Magnis-Suseno, Franz, Pemikiran Karl Marx, Gramedia, Jakarta, 1999. 37 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 42. 162 Konsep ini tidak hanya berlaku untuk para agamawan semata, tetapi juga untuk media massa, universitas, dan kaum intelektual yang menggunakan kekuatan mereka justru untuk membenarkan ketidakadilan dan penindasan yang ada. Mereka semata menjadi alat untuk melayani dan membenarkan sistem yang telah ada, yang tidak adil dan menindas. Di hadapan semua ini, lahirlah intelektual kaum pekerja yang memiliki semangat untuk membongkar sekaligus melampaui “dosa dan takhayul-takhayul dari pasar”.38 (sins and superstitions of market) Mereka juga hendak mengembalikan atmosfer demokratis dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan para pemilik modal dan penguasa politis korup kepada rakyat.39 Seperti sudah disinggung sebelumnya, tujuan utama pendidikan, sebagaimana dijabarkan oleh Chomsky, adalah menciptakan manusiamanusia bebas yang dapat saling berhubungan satu sama lain dengan setara. Hanya di dalam situasi inilah, menurutnya, manusia bisa menghasilkan karyakarya kreatif. Kreativitas hanya bisa lahir dari kebebasan, karena kebebasan adalah tanda dari keluhuran martabat manusia.40 Wilheml von Humboldt, pemikir Jerman, sebagaimana dikutip oleh Chomsky, pernah menulis begini, “Ketika orang menghasilkan sesuatu karena diperintah, kita bisa menghargai apa yang ia lakukan, tetapi kita mencela dirinya, karena dia bukanlah manusia sejati yang bertindak berdasarkan dorongan dan keinginannya.”41 Sistem ekonomi pasar kapitalisme, yang kini mendikte dunia pendidikan dunia, justru mengedepankan perintah, daripada kebebasan untuk berkarya. Orang yang bekerja pada seorang pemilik modal jelas harus mematuhi perintah dari sang pemilik modal tersebut. Banyak dari mereka bekerja bukan karena dorongan hati, melainkan dari keterpaksaan semata. Orang semacam inilah yang dianggap Humbolt sebagai orang “terbodoh yang pernah hidup di dalam 38 Ibid. 39 Ibid. 40 Kreativitas perlu kebebasan dan, menurut saya, fokus. Ini adalah pendapat yang dapatkan dari refleksi atas tulisan-tulisan Nietzsche dan Peter Drucker, pakar manajemen dunia abad 20. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di http://rumahfilsafat.com/2010/07/06/friedrich-nietzsche-dan-peter-druckerberdiskusi-tentang-bisnis-dan-kreativitas/ 41 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 42. 163 sejarah manusia.”42 Ekonomi pasar kapitalisme tidak membuat orang bebas, tetapi justru sebaliknya, yakni membuat orang menjadi budak dari modal. Pertentangan antara rakyat dengan kelas pemilik modal di AS, menurut Chomsky, sudah setua sejarah bangsa AS itu sendiri. Thomas Jefferson, salah seorang bapak bangsa AS, melihat terciptanya ketegangan di dalam masyarakat AS antara kelompok aristokrat di satu sisi, dan kelompok demokrat di sisi lain. Secara sederhana, Jefferson, sebagaimana ditulis oleh Chomsky, menyatakan, bahwa kelas aristokrat adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya pada rakyat, dan bernafsu untuk mengumpulkan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka percaya, bahwa ada orang-orang yang lebih layak mendapatkan kekuasaan, karena mereka adalah manusia dengan kualitaskualitas diri yang lebih tinggi, daripada manusia-manusia lainnya. Di sisi lain, kaum demokrat adalah orang-orang yang mengambil posisi sebagai rakyat, percaya pada kebaikan dan kemampuan rakyat untuk mengelola dirinya sendiri, serta bersedia untuk selalu memperjuangkan kepentingannya.43 Dua kelas tersebut kini berkembang. Kaum aristokrat menjadi penyokong kapitalisme murni dengan pengejaran untuk serta pengembangan modal melalui beragam cara. Sementara kaum demokrat tepat menjadi anti tesis dari kaum aristokrat, yakni sebagai pejuang hak-hak rakyat umum, dan menolak adanya aritokratisme ataupun elitisme dalam bentuk apapun di dalam tata kelola politik.44 Di dalam perjalanan waktu, para pemilik modal, yakni kaum kapitalisaristokrat, berhasil memperoleh kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut, 42 Ibid, hal. 43. 43 Kita masih dengan mudah menemukan pembedaan antara dua kelas sosial tersebut sekarang ini. Wacana pertarungan antara demokrasi dan kapitalisme, karena perbedaan nilai-nilai yang dianut keduanya, bisa dengan tajam kita simak dalam Herry Priyono, B, Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005, terutama di dalam tulisan Ignatius Wibowo. Beliau menunjukkan dengan jelas, bahwa demokrasi dan kapitalisme tidak selalu berjalan selaras, bahkan seringkali meniadakan satu sama lain. Saya rasa uraian beliau tepat menunjukkan tegangan yang terjadi di Indonesia antara kelompok pro demokrasi di satu sisi, dan para pemilik modal raksasa di sisi lain yang ingin memaksakan agenda-agenda politis yang menguntungkan mereka. Tegangan ini semakin tajam, dan rakyat menjadi korban, ketika pemerintah di Indonesia diam tak berbuat apa-apa, seperti sekarang ini. 44 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 43. 164 menurut Chomsky, tidak datang dari rakyat maupun prosedur-prosedur demokrasi, melainkan dari pendekatan personal dan finansial pada penguasapenguasa politis.45 Para kapitalis-aristokrat menguasai bank-bank raksasa, dan seringkali, dengan kekuatan finansial yang mereka punya, mendikte berbagai kebijakan publik. Dengan cara ini, kekuatan finansial mereka pun semakin besar, karena mereka berhasil memaksakan kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan mereka, sekaligus merugikan pihak-pihak lainnya.46 Proses ini membawa perubahan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Orang tidak lagi diukur dari kualitas dirinya, tetapi dari berapa uang dan kuasa yang ia punya, tak peduli uang dan kuasa itu didapat dari mana. Proses-proses politik demokrasi pun ditunggangi oleh kekuatan uang yang hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, sambil mengorbankan kelompok masyarakat lainnya. Pola kekuasaan para penguasa bisnis di dalam masyarakat kapitalis liberal sebenarnya, menurut Chomsky, tidak jauh berbeda dengan pola kekuasaan rezim-rezim otoritas berkedok Marxisme-Komunisme pada abad ke-20. Keduanya rakus, dan tak takut untuk mengorbankan manusia maupun kelompok lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Buktinya adalah transisi yang dialami oleh negara-negara bekas komunis, setelah Uni Soviet runtuh di akhir abad 20 lalu. Para elit bekas partai komunis segera berubah menjadi pebisnis-pebisnis baru yang secara agresif melakukan transaksitransaksi global bagaikan seorang kapitalis global.47 Sebelumnya mereka berteriak soal pentingnya sosialisme dan komunisme di tata kelola politik. 45 Ibid, hal. 44. 46 B. Herry Priyono menyebutnya sebagai “Leviathan kedua”, yakni bangkitnya otoritas lain di samping negara yang memiliki kekuatan sama, bahkan lebih, dari negara itu sendiri. Dengan modal yang begitu besar, dan jaringan internasional yang luas, perusahaan-perusahaan multinasional menerjang masuk berbagai negara, menghisap sumber daya dengan harga murah, dan membuat pemerintah setempat seolah tak berdaya di hadapannya. Lihat harian Kompas 5 April 2002, “Memahami Leviathan Baru” 47 Keduanya serupa, karena keduanya memusuhi hal yang sama, yakni kebebasan dan kesetaraan antar manusia. Keduanya tidak menghendaki adanya manusiamanusia yang kreatif dan setara, karena keberadaan manusia-manusia semacam itu justru menganggu kepentingan-kepentingan ekspansi kekuasaan modal maupun politik mereka. Saya pikir, ini adalah salah satu poin penting dari argumen Chomsky. 165 Namun sebagaimana dicatat Chomsky, setelah Soviet roboh, mereka menjadi agen-agen pro kapitalisme dan pasar bebas yang amat antusias. “Pergerakan itu”, demikian Chomsky, “sebenarnya amat mudah karena ideologi dasarnya adalah sama....pergerakan dari Stalinisme menjadi ‘merayakan Amerika’ cukup biasa di dalam sejarah modern, dan itu tidak perlu melakukan perubahan banyak dalam soal nilai-nilai, hanya perlu perubahan penilaian tentang dimana kekuasaan berada.”48 Apa dampak dari semua ini, yakni dari otoritas kekuasaan yang menerkam kebebasan, dan menciptakan kesenjangan yang semakin besar dalam masyarakat? Yang tercipta kemudian adalah suatu masyarakat yang diwarnai ketidakadilan dan ketidakpedulian. Di Indonesia sekarang ini, banyak orang curiga dan pesimis pada dunia politik. Sedikit sekali yang berpendapat, bahwa para pemimpin politik kita mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Chomsky, pola semacam ini adalah hasil dari pola pendidikan yang menindas cara berpikir kritis, dan mencegah manusia untuk menjadi manusia-manusia yang setara.49 Para politisi kita, menurut saya, adalah “produk” dari sistem pendidikan yang seperti itu. Sistem politis yang ada, mulai dari pelayanan kebutuhan dasar sampai dengan kebijakankebijakan publik yang memiliki dampak luas, seolah memaksa kita sebagai warga negara untuk menjadi apatis, yakni menjadi tidak peduli.50 Di hadapan situasi itu, Chomsky mengajak kita justru untuk aktif berpolitik, karena hanya politiklah satu-satunya area, di mana warga negara bisa sungguh berpartisipasi, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk semua. Cengkraman otoritas kekuasaan bisnis terhadap ranah politik sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh Adam Smith dan John Dewey. Cengkraman ini membuat mayoritas rakyat tidak lagi peduli pada politik dalam arti 48 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 44. 49 Ibid, hal. 54. 50 Di hadapan situasi yang membuat kita tidak peduli dan kecil hati, justru panggilan untuk lebih berpartisipasi perlu untuk didengar, dan dijalankan. Hal ini tidak hanya benar di AS, tempat Chomsky hidup dan berkarya, tetapi juga untuk Indonesia. Kita menderita karena politik yang tak dikelola secara tepat. Namun solusi untuk masalah itu pun hanya satu, yakni ambil bagian aktif dalam politik, dan berjuang untuk membuat perubahan. Ajakan yang sudah tua sekali, namun amat sedikit yang menjalankannya. 166 sebenarnya, melainkan sekedar terkurung di dalam pemburuan kenikmatan pribadi mereka, sekaligus menumpuk modal untuk kepentingan pribadi mereka. Dengan kata lain, perkembangan kekuasaan bisnis di dalam kehidupan publik mengancam kualitas demokrasi di dalam masyarakat itu sendiri, dan itu juga berarti mengancam berbagai usaha untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama dengan cara-cara yang partisipatif.51 Di akhir pemaparannya, Chomsky mengajak kita untuk memilih, apakah akan menjadi seorang demokrat (democrats) yang percaya pada rakyat dan prosesproses demokratis untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, atau menjadi seorang aristokrat yang percaya, bahwa hanya elit ekonomi maupun politik yang bisa membawa perubahan pada masyarakat. Jika menjadi seorang demokrat, anda harus siap untuk berjuang jatuh bangun untuk menciptakan kebaikan bersama melalui proses-proses demokratis yang panjang dan melelahkan. Jika menjadi seorang aristokrat (aristocrats), anda akan dibuai dengan kekuasaan dan kekayaan. Dua hal yang selalu menggoda manusia untuk keluar dari jalur untuk memperjuangkan kebaikan bersama.52 4. Kesimpulan dan Catatan Kritis Pada hakekatnya sebagaimana tersirat di dalam tulisan Chomsky, demokrasi dapat dipandang sebagai asosiasi orang-orang yang berpikiran bebas yang bekerja sama sebagai orang-orang yang setara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran melalui usaha bersama. Inilah ideal negara demokratis yang kini menjadi cita-cita bangsa Indonesia di dalam tata kelola politiknya. Menurut Chomsky, pendidikan pun harus mengabdi pada citacita itu, yakni sebagai proses untuk menciptakan orang-orang bebas, yang mampu menjalin hubungan secara setara dengan orang-orang di sekitarnya, dan bekerja sama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui proses-proses demokratis.53 Dengan kata lain, bagi Chomsky, pendidikan 51 Chomsky, Noam, Democracy and Education, ... hal. 55. 52 Apa yang terjadi pada massa Jefferson dan masa kita hidup sekarang, menurut Chomsky, memang berbeda. Namun pilihan fundamental yang perlu dibuat tetaplah sama, yakni menjadi seorang demokrat, atau seorang aristokrat. 53 Pendapat serupa juga dengan sangat baik dilontarkan oleh pakar pendidikan asal Inggris yang kini menetap di Amerika Serikat, Ken Robinson, dalam bukunya yang berjudul Robinson, Ken, The Element, Penguin Group, New York, 167 adalah upaya untuk menciptakan manusia-manusia demokratis. Di dalam merumuskan pandangan ini, Chomsky amat dipengaruhi oleh John Dewey dan pemikiran Marxis. Dua ide ini, yakni makna demokrasi dan peran pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis, pada hemat saya, amat relevan untuk situasi Indonesia sekarang ini. Dalam konteks Indonesia, saya melihat setidaknya dua tantangan di dalam upaya untuk mewujudkan konsep pendidikan manusia-manusia demokratis yang menjadi nilai ideal Chomsky. Yang pertama pola berpikir otoriter yang melekat pada tradisi maupun agama di Indonesia. Yang kedua adalah pola berpikir kapitalistik, di mana penumpukan modal adalah hal utama, yang menjadi paradigma dominan di kota-kota besar Indonesia. Dua hal ini mengancam kebebasan manusia, dan menciptakan kultur feodal di dalam masyarakat, yakni kultur yang menyatakan, bahwa di dalam masyarakat, ada sekelompok orang yang memiliki status lebih tinggi, baik secara religius maupun ekonomis, daripada orang lainnya. Pada hemat saya, dua paradigma ini begitu dominan menancap di dalam benak rakyat Indonesia, dan menjadi tantangan terbesar bagi terciptanya pendidikan manusia-manusia demokratis yang dicita-citakan oleh Chomsky. Saya juga memiliki dua catatan kritis atas pandangan Chomsky. Yang pertama, di dalam masyarakat modern terglobalisasi sekarang ini, masyarakat membutuhkan hadirnya orang-orang yang memiliki ketrampilan teknis dan spesifik, seperti dokter gigi, ahli listrik, ahli fondasi bangunan, ahli struktur bangunan, dokter spesialis jantung, dokter bedah, dokter ahli kanker, dan sebagainya. Kehadiran mereka mutlak dibutuhkan, terutama untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern terglobalisasi yang memang amat rumit dan spesifik. Maka pada hemat saya, pendidikan manusia-manusia demokratis harus juga bisa berjalan berbarengan dengan pendidikan berbasis keahlian teknis spesifik yang memang amat dibutuhkan sekarang ini. Saya menyebutnya paradigma pendidikan demokratik spesialis. Saya pikir ini bisa menjadi catatan yang menarik untuk mengembangkan ide-ide dasar yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Chomsky. 2009. Ia berpendapat, bahwa kebebasan akan melahirkan kreativitas, dan akan menciptakan hal-hal luar biasa yang sebelumnya tak terpikirkan. Pendidikan harus memberikan ruang gerak bagi imajinasi dan kreativitas peserta didik (kebebasannya). 168 Yang kedua, Chomsky membedakan antara kaum demokrat dan aristokrat. Pembedaan ini dibuatnya dengan mengikuti pembedaan yang telah dilakukan oleh Thomas Jefferson di masa-masa awal kemerdekaan Amerika Serikat. Kita perlu bertanya, apakah pembedaan itu masih relevan sekarang ini? Pada hemat saya, seperti segala bentuk pembedaan di dalam lingkungan sosial manusia, pembedaan tidak pernah mutlak. Itulah yang sekarang ini terjadi di dalam pembedaan antara kaum demokrat dan aristokrat. Dalam konteks Indonesia, sejauh saya amati, pendulum telah berubah. Banyak sekali percampuran ganjil antara kaum aristokrat dan demokrat yang justru menjadi penggerak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tokoh-tokoh di Indonesia di awal abad ke-21, seperti Dahlan Iskan dan Joko Widodo, adalah kaum aristokrat, karena mereka adalah pengusaha yang cukup berhasil di bidangnya, namun sekaligus seorang demokrat, karena mereka menempatkan kepentingan rakyat di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka buat, dan mengajak rakyat untuk bekerja demi terciptanya kebaikan bersama. Sosok aristokrat berjiwa demokrat, inilah yang pada hemat saya belum dipikirkan lebih dalam oleh Chomsky. Di abad 21 ini, lahirnya konsep-konsep hibrida, seperti pendidikan demokratik-spesialis, dan pemimpin aristokrat berjiwa demokrat, menjadi obyek kajian menarik yang perlu dicermati lebih dalam. Reza A.A. Wattimena Alumnus Program Sarjana dan Magister Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Pengajar Filsafat Politik dan dosen tetap di Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya. Aktif menulis di berbagai media serta mempublikasikan buku-buku bacaan yang kental dengan nuansa refleksi filosofis dan pencerahan. Dapat dihubungi di [email protected]. DAFTAR RUJUKAN Chomsky, Noam, Democracy and Mis-Education, Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2005 Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan di Negara Orde Baru, Gramedia, Jakarta, 1993. 169 Garland, Christian, International Encyclopedia of Revolution and Protest, Immanuel Ness, ed., Blackwell Publishing, 2009. Kelly, Mark G.E., The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge, London, 2009. Priyono, B. Herry (ed), Sesudah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2005. Wardaya, Baskara, Bung Karno Menggugat, Galang Press, Yogyakarta, 2009. Robinson, Ken, The Element, Penguin Group, New York, 2009. Stiglitz, Joseph, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Company, USA, 2002. Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kritis Immanuel Kant, Evolitera, Jakarta, 2010. Wattimena, Reza A.A., Filsafat Kata, Evolitera, Jakarta, 2011. Internet: http://rumahfilsafat.com/2010/07/06/friedrich-nietzsche-dan-peterdrucker-berdiskusi-tentang-bisnis-dan-kreativitas/ http://www.chomsky.info/bios/2009----.htm (7 Maret 2012 jam 17.00) http://www.itb.ac.id/news/3441.xhtml pada 2 April 2012, 15.00. 170 RESENSI BUKU 1 Judul Buku : Filsafat Anti-Korupsi. Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi. Penulis : Reza A. A. Wattimena Terbitan : Kanisius, Yogyakarta 2012 Tebal : 201 halaman Buku ini berjudul Filsafat Anti-Korupsi. Penulis mengklaim buku ini sebagai buku yang untuk pertama kalinya tidak secara teknis mendekati permasalahan korupsi dari aspek hukum, politik, atau ekonomi, melainkan dari sisi-sisi terdalam manusia yang melakukannya (catatan pada cover luar bagian belakang). Dari hakekatnya, filsafat memang senantiasa menggarap sisi-sisi fundamental dari hidup manusia. Filsafat memang tidak pernah puas dengan apa yang nampaknya beres-beres saja. Globalisasi dan pluralitas hidup modern tidak jarang menghempaskan manusia pada banalitas kehidupan dan pragmatisme. Tetapi kodrat manusia sebagai makhluk yang berkehendak bebas dan berakal budi senantiasa mau mencari makna yang lebih dalam atas kehidupannya. Dia tidak menyerah begitu saja pada fragmentasi yang bersifat parsial tanpa orientasi ke depan. Kehidupan yang terjebak hanya dalam kekinian yang pragmatis tidak menjanjikan dan tidak memberikan harapan apa-apa selain kegelapan, ketiadaan (nothingness), dan disorientasi. Kompleksitas hidup manusia modern dengan demikian bukan hanya membutuhkan kajian dalam perspektif sosiologis, antropologis, atau psikologis-sosial, tetapi juga perspektif filosofis-sosial. Korupsi adalah wajah buram kehidupan manusia modern yang dikuasai oleh kepentingan kekuasaan. Maka bentuk korupsi yang pertama adalah korupsi politik. “Penggunaan kekuasaan sebagai pejabat negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga dapat disebut korupsi” (hal. 4). “Biasanya korupsi amat tersebar luas dan tertanam amat dalam di 171 sistem politik dan ekonomi negara-negara berkembang” (idem). Keburaman wajah hidup manusia oleh korupsi berkait-mengkait antara politik kekuasaan, buruknya sistem dan pranata normatif dalam bentuk produk-produk hukum yang tidak adil dan bias kepentingan politik, serta perilaku korupsi yang sudah meng-kultur (menjadi semacam second nature). Akibatnya adalah kehancuran kehidupan sosial dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai lembaga yang sanggup mengayomi, melindungi, dan menyejahterakan. Korupsi juga mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan hancurnya ke-saling-percaya-an antar warga masyarakat. Oleh karena itu, perilaku korupsi menjadi sangat fenomenal dan sekaligus memprihatinkan semua orang yang masih bekehendak baik dan mendambakan peradaban kehidupan yang bermartabat manusia. Dengan kaca mata filsafat, atau dengan menggunakan filsafat sebagai pisau bedah, fenomena perilaku korupsi dilihat bukan hanya semata dari akibat-akibat yang langsung nampak dan bisa dirasakan demikian destruktif bagi kehidupan bersama, tetapi terutama bila dilihat dari motivasi-motivasi dasar manusia. Dari kaca mata filsafat, korupsi di sini dipahami sebagai “ekspresi dari situasi manusiawi kita sebagai manusia, yakni karena kita memiliki hasrat berkuasa, gemar berburu kenikmatan, memiliki sisi-sisi hewani yang brutal ...” (hal. 12). Kaca mata filsafat melihat pelaku korupsi pertama-tama sebagai manusia yang juga memiliki kerumitan dan dinamika jiwa yang unik. Maka, pelaku korupsi secara filosofis tidak dihakimi pertamatama sebagai yang harus segera diusut dan dibawa ke ranah hukum, tetapi sebagai manusia pada umumnya. Aspek inilah persisnya yang membedakan antara pendekatan filsafat dengan aspek hukum, politik, maupun ekonomi. Dalam kaca mata filsafat, sisi-sisi terdalam manusia pelaku korupsi mendapatkan sorotannya secara tajam, reflektif, dan rasionil. Bab 1 buku ini menyoroti korupsi dalam kaitannya dengan hasrat manusia untuk berkuasa. Filsuf paling tepat untuk dirujuk tentunya adalah Nietzsche. “Nietzsche menggunakan konsep kehendak untuk berkuasa sebagai model untuk menjelaskan alam semesta beserta manusia yang ada di dalamnya.” (hal. 40). Kehendak untuk berkuasa adalah kodrat alamiah sebagai struktur fundamental kehidupan manusia. Sebagai daya gerak motivator terkuat manusia, kehendak untuk berkuasa bisa bersifat destruktif. 172 Bab 2 menyoroti kaitan antara korupsi dengan sifat manusia sebagai pemburu kenikmatan. Untuk kajian ini, penulis mengacu pada filsuf bernama Donatien Alphonse Francois de Sade atau disingkat de Sade. “Bagi de Sade, korupsi adalah bentuk konkret dari pemburuan kenikmatan tanpa batas yang dilakukan oleh manusia, yang selalu diselubungi oleh kemunafikan penampilan dan pencitraan” (hal. 66). Korupsi merajalela dan tidak pernah mencuatkan keinginan untuk “sembuh” dari kecanduannya ketika sikap dasar manusia pertama-tama adalah mengutamakan kesenangan, kenikmatan, pleasure, di satu sisi, dan di sisi lain manusia malu-malu untuk mengakui sikap dasar ini. Yang termanifestasikan pada akhirnya adalah kemunafikan: korupsi dipraktekkan dalam keseharian hidup di satu sisi, sementara di sisi lain keluhuran dan kemuliaan religius dikotbahkan, moralitas diajarkan, sikap-sikap etis-moralistis dianggap sebagai bagian dari adat “ketimuran”. Perilaku korupsi jg bisa disoroti dari kaitannya dengan sisi hewani dari kodrat manusia. Tulisan yang bisa ditemukan di bab 3 buku ini mendeskripsikan keterkaitan sosiologis-filosofis yang cukup rumit antara massa dan kekuasaan. Sisi hewani manusia termanifestasikan dalam agresivitasnya, kecenderungannya menjadi massif dan anonim di tengah kerumunan dan massa mengambang, serta metode kekerasan irasional yang dilahirkan oleh massa tak berbentuk namun penuh dengan aroma kekuasaan dan kepentingan politik. Ketika sifat jahat dan sisi hewani tak terkendali mentransformasi menjadi perilaku massif, orang merasa wajar dan sah-sah saja ketika bersama-sama dengan banyak orang melakukan apa yang sebetulnya in se sungguh-sungguh jahat. Pemikiran yang berangkat dari gagasan Hannah Arend ini terungkap dalam bab 4. “Dari pemikiran Arendt kita bisa mengajukan satu argumen kontroversial, bahwa kejahatan terbesar justru dilakukan oleh orang-orang biasa yang tidak merasa melakukan tindakan jahat, tetapi melihat kejahatan semata sebagai sesuatu yang wajar” (hal. 116). Kejahatan pun bisa dilihat secara simbolis (bab 5). Kejahatan diyakini telah terjadi dalam sejarah manusia sejak awal-mula yang secara mitologisreligius nampak dalam “wajah” dosa, tabu, noda, ketidakmurnian, dan lain sebagainya. “Dosa adalah suatu bentuk pemberontakan manusia pada Tuhannya.” (hal. 129). Untuk itu, diciptakanlah ritus-ritus pemurnian diri dari 173 bentuk-bentuk kejahatan tersebut yang mana semua ritus mengarah kepada pemurnian, pertobatan, dan rekonsiliasi. Dalam dua bab terakhir (6 dan 7) penulis melihat korupsi sebagai bentuk kejahatan sistemik serta hubungan antara korupsi dan kekosongan jiwa. Korupsi telah menghancurkan sisi-sisi kemanusiaan fundamental baik kehancuran pribadi (personal) maupun sosial (kehancuran sendi-sendi hidup bersama sebagai manusia bemartabat). Penulis di bagian akhir mengajukan beberapa pemikiran yang diperlukan agar kehidupan berbangsa ini mampu “melampaui” korupsi. Pertama adalah penataan kembali sistem kepartaian dan sistem hukum agar berorientasi pada fungsinya sebagai “pelayan rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama” (hal. 199). Kalau perlu dengan cara pemaksaan agar kaidah etis itu diindahkan oleh kedua lembaga publik tersebut. Penulis dalam hal ini hanya berhenti di sini dan tidak meneruskannya pada tataran praktis soal bagaimana persisnya pemikiran tersebut direalisasikan dalam kehidupan bersama sebagai lembaga masyarakat. Menurut hemat kami, penulis nampaknya memang tidak sedang menulis sebuah buku manual praktis tentang bagaimana memberantas korupsi. Penulis sedang mencoba meneropong dan mengkaji fenomena korupsi dari sudut pandang filsafat sebagai ilmu reflektif-sosial. Oleh karena itu, poin ke dua yang diajukan penulis (dan ini “sungguh” bernuansa filosofis) adalah dengan mengetengahkan sikap transendensi diri. Artinya, dengan kajian reflektif atas diri, menjaga jarak dengan diri sendiri, lantas menemukan dan menyadari sisi-sisi “gelap” kemanusiaan kita yang secara potensial juga bisa terlibat dalam perilaku korupsi. Kesadaran diri ini disebut dengan transendensi diri yang mengharapkan pembaharuan hidup manusia sebagai yang bermartabat (mengingat dan menyadari bahwa perilaku korupsi tak ubahnya dengan perendahan martabat manusia sebagai manusia, dehumanisasi). Sesuai dengan judulnya, buku ini memang mencoba memanfaatkan kajian reflektif-filosofis untuk menyoroti masalah sosial-aktual di negeri ini, yaitu korupsi. Sebagai sebuah upaya akademis, buku ini layak diacungi jempol. Namun, tanpa mengurangi apresiasi atas usaha ini, langkah-langkah penyempurnaan juga layak dilakukan mengingat kajian-kajian filsafat seringkali bukan bacaan yang dengan mudah bisa langsung dimengerti dan dipahami oleh pembaca pada umumnya (apalagi pembaca yang tidak 174 berlatarbelakang pendidikan dan pengetahuan filsafat sebagai ilmu). Banyak terminologi filosofis yang seringkali belum familiar bagi sebagian pembaca. Selain itu, kajian yang dalam tiap bab menyitir dari (bahkan menyandarkan gagasan-gagasan utamanya pada) pelbagai bahan bacaan dan buku referensi membuat tulisan-tulisan dalam buku ini lebih bersifat panoramic dari pada sebuah kajian yang bersifat komprehensif-holistik-integral tentang tema korupsi itu sendiri. Tentu hal tersebut tidak mengurangi apresiasi terhadap penulis dalam keikutsertaannya memperkaya khasanah pengetahuan sisi-sisi kemanusiaan dari manusia abad ke 20-21 dengan dinamikanya yang tidak jarang mengejutkan namun sekaligus menantang untuk terus-menerus digali dan dipahami. Hanya dengan usaha semacam ini kita berharap membuat hidup kita “berdamai” dengan diri sendiri dan orang lain serta menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat sebagai manusia. Emanuel Prasetyono 175 RESENSI BUKU 2 Judul Buku : Filsafat Pra Skolastik Eropa. Pengenalan Singkat Sejarah Filsafat Abad Pertengahan. Penulis : Ramon Nadres Terbitan : Zifatama, 2012 Tebal : 74 halaman Buku ini tentang Filsafat Pra Skolastik. Mengapa Filsafat Pra Skolastik? Mana sajakah yang termasuk Filsafat Pra Skolastik? Di kalangan umum, filsafat ini tidak terlalu dikenal sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya di bagian Prakata (hal. iii). Buku tentang filsafat Abad Pertengahan dalam bahasa Indonesia hampir tidak diketemukan. Sadar akan pertanyaan-pertanyaan dasar ini, penulis memulai buku ini dengan uraian berlatar belakang historis tentang Filsafat Pra Skolastik yang membedakannya dari filsafat dari latar belakang sejarah lainnya, semisal dari Filsafat Yunani atau Filsafat Modern. Penulis mengawali penjelasannya dengan Filsafat Yunani Kuno. Filsafat Yunani Kuno merepresentasikan cikal-bakal sejarah pergumulan rasional manusia dalam memahami realitasnya, dirinya sendiri, sesamanya, alam sekitarnya, dan Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para filsuf Yunani mencoba mengusahakan penjelasan-penjelasan rasional atas realitasnya (melawan penjelasan-penjelasan yang bersifat mitologis yang telah berkembang selama berabad-abad). Para filsuf Yunani mengawali pergumulan rasional itu dengan pencarian atas akar, sebab, atau asas-asas prinsipiil dari segala sesuatu. Alam semesta dikaji dan dipahami dalam terang dan bimbingan rasional-kodratiah manusia. Selanjutnya, kemunculan para sofis (dan secara khusus Sokrates) menandai suatu titik balik “kesibukan” pergumulan rasional filsafat. Perilaku manusia, standard kebaikan dan keburukan, serta etika hidup dan kebahagiaan menjadi tema-tema yang mulai menarik untuk dikaji dan dianalisis. Titik balik semacam ini untuk selanjutnya menjadi tanda yang amat penting untuk melihat dan memahami filsafat 176 sebagai perjalanan sejarah pergumulan rasional manusia (sejarah pemikiran) dalam memahami dan memaknai realitas hidupnya. Lalu dari mana kita memulai sejarah Filsafat Pra Skolastik ini? Apa yang menjadi titik balik Filsafat Pra Skolastik yang menandai pergumulan rasional manusia dalam jamannya? Filsafat Pra Skolastik bersama dengan Filsafat Skolastik adalah bagian dari Filsafat Abad Pertengahan. Kemunculannya terdorong oleh kristianitas yang menguat sebagai ajaran iman yang mendominasi pada jaman itu. Pola-pola refleksi dan penalaran logis ala filsafat Plato dan Plotinos, misalnya, “dimanfaatkan” untuk menganalisis dan menjelaskan misteri-misteri iman yang pada jaman itu masih berusaha menemukan rumusan-rumusan dogmatis-doktrinal. Di sinilah para filsuf Pra Skolastik secara kontinyu bisa berganti-ganti peran antara menjadi seorang filsuf, teolog, atau Bapa-bapa Gereja. Bagaimana “memanfaatkan” metodologi filsafat untuk penjelasanpenjelasan misteri iman? Bukankah metodologi penjelasan-penjelasan dan telaah filsafat yang rasional amat berbeda dengan metodologi iman yang amat menyandarkan diri pada pewahyuan, tradisi, otoritas, dan doktrin? Dengan kata lain, bagaimana menjelaskan relasi antara akal budi dan iman? Sebagaimana dikatakan oleh penulis buku ini: “Pengetahuan yang sejati, baik alamiah maupun supranatural, dapat diperoleh melalui penggunaan filsafat. Filsafat, sesuai dengan arti aslinya yakni cinta akan kebijaksanaan, dapat mengungkap apa yang benar di dalam setiap bentuk pengetahuan, jika memang ada kebenaran di dalam pengetahuan itu.” (hal 11). Terkenallah apa yang disebut dengan philosophia ancilla theologiae, filsafat adalah hamba atau pembantu perempuan dari teologi. Tetapi, dalam perjalanan sejarahnya, filsafat ternyata tidak hanya sekedar menjadi pembantu perempuan bagi teologi saja. Sebab, ternyata filsafat justru di dalam perannya itu menemukan bentuk-bentuk sistematisnya. Bahkan ditemukan konsep-konsep baru yang tidak terduga sebelumnya berkat pelbagai refleksi dan penalaran logis yang dikembangkan oleh filsafat (hal. 15). Demikianlah sesungguhnya Filsafat Pra Skolastik dan Filsafat Skolastik dalam rangkaian sejarah Filsafat Abad Pertengahan menyajikan kepada kita suatu “pentas” ketegangan intensif pergumulan antara iman 177 dan akal budi, antara filsafat dan teologi. Lebih tepat sebetulnya dikatakan bahwa masa Filsafat Pra Skolastik adalah masa pergumulan dan ketegangan metodologis dalam mengenali dan memahami realitas hidup sebagai orang beriman kristiani dan sekaligus sebagai manusia yang berakal budi dan berkehendak bebas. Disebut pergumulan dan ketegangan metodologis karena pendekatan terhadap realitas hidup dilakukan baik sebagai orang beriman kristiani maupun sekaligus sebagai manusia yang secara kodrati berakal budi (rasional). Sebagai orang beriman kristiani, pendekatan dan pemahaman terhadap realitas hidup mau menyandarkan diri pada metodologi iman (doktrin, ajaran, otoritas atau magisterium, tradisi, dan revelasi). Sebaliknya, sikap manusia sebagai makhluk berakal budi secara progresif menyandarkan argumentasi-argumentasinya pada penalaran akal budi (logika) yang bersifat kodrati. Bisa dibayangkan, menggali pemikiran dan refleksi dari tulisan-tulisan para filsuf Pra Skolastik jelas merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, penulis membatasi diri pada beberapa filsuf yang merepresentasikan titik-titik balik tertentu dalam tema-tema filsafat yang digumuli pada jaman Pra Skolastik. Ada 3 filsuf yang digarap oleh penulis yang dipandangnya representatif masing-masing pada jamannya, yaitu John Scotus Eriugena, Anselmus dari Canterburry, dan Petrus Abelardus. Ketiga filsuf ini sekaligus menandai terbukanya jaman yang membawa pergumulan dan ketegangan antara iman dan akal budi ke ranah akademis, ke ruang-ruang kelas universitas. Di sana, di kelas-kelas itu, “pentas” yang disebut Filsafat Skolastik menjadi ajang yang menarik bagi sejarah pemikiran manusia. Buku ajar ini memang sebuah pengantar yang bisa ditilik dari jumlah halaman dan penjelasan-penjelasannya yang singkat dan padat. Pembaca akan sedikit kecewa kalau mengharapkan sebuah buku yang detail dan terperinci dalam menjelaskan pemikiran-pemikiran dan latar belakang sejarah para filsuf Pra Skolastik. Tetapi dari pengantar ini diharapkan para pembaca sedikit banyak menemukan gambaran sejarah kelahiran “suasana akademik yang ketat dan mendalam di antara sekolah-sekolah urban” (hal. 73) yang pada akhirnya melahirkan universitas-universitas. Penulis menutup buku pengantar yang ringkas ini dengan kalimat bijak: “Sangatlah 178 mengagumkan jika kita menyadari bahwa tiga agama monoteistik, yakni Yudaisme, Kristen, dan islam, sebenarnya menjadi inspirasi dan dorongan untuk penyelidikan filosofis yang rasional. Dari sudut pandang ini, kita dapat menolak segala argumen yang menyatakan bahwa agama adalah musuh dari akal budi dan kebenaran itu sendiri.” (hal 74). Emanuel Prasetyono