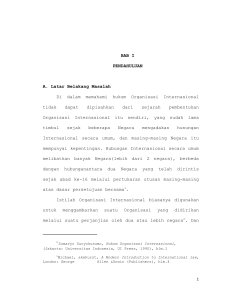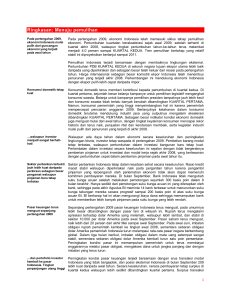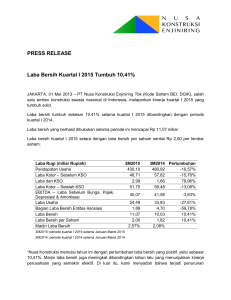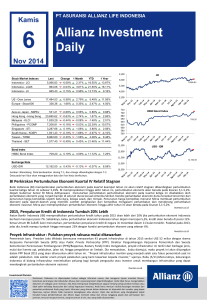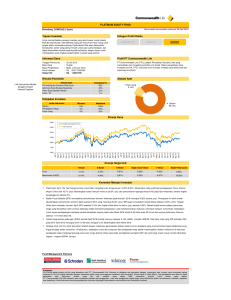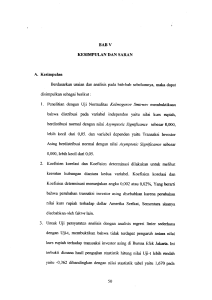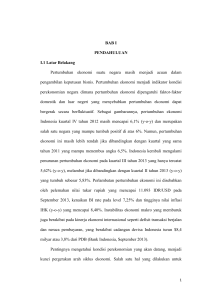Eropa, Kita, dan 2012 1 Oleh Arianto A. Patunru 2 Brussels, awal
advertisement
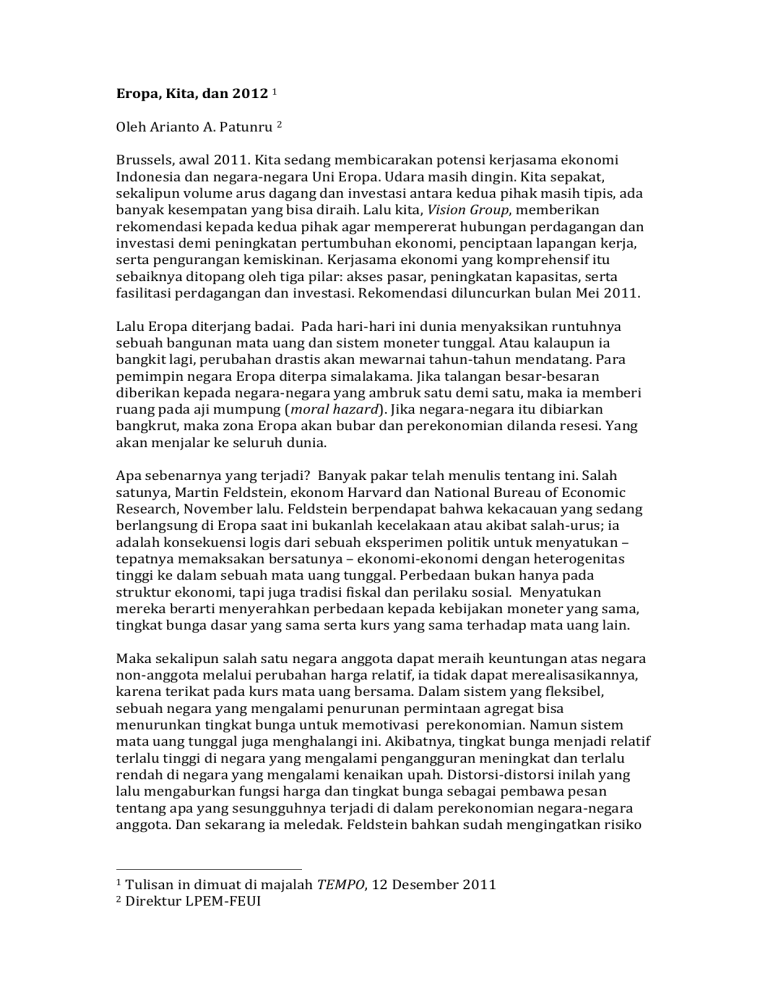
Eropa, Kita, dan 2012 1 Oleh Arianto A. Patunru 2 Brussels, awal 2011. Kita sedang membicarakan potensi kerjasama ekonomi Indonesia dan negara-­‐negara Uni Eropa. Udara masih dingin. Kita sepakat, sekalipun volume arus dagang dan investasi antara kedua pihak masih tipis, ada banyak kesempatan yang bisa diraih. Lalu kita, Vision Group, memberikan rekomendasi kepada kedua pihak agar mempererat hubungan perdagangan dan investasi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan. Kerjasama ekonomi yang komprehensif itu sebaiknya ditopang oleh tiga pilar: akses pasar, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi perdagangan dan investasi. Rekomendasi diluncurkan bulan Mei 2011. Lalu Eropa diterjang badai. Pada hari-­‐hari ini dunia menyaksikan runtuhnya sebuah bangunan mata uang dan sistem moneter tunggal. Atau kalaupun ia bangkit lagi, perubahan drastis akan mewarnai tahun-­‐tahun mendatang. Para pemimpin negara Eropa diterpa simalakama. Jika talangan besar-­‐besaran diberikan kepada negara-­‐negara yang ambruk satu demi satu, maka ia memberi ruang pada aji mumpung (moral hazard). Jika negara-­‐negara itu dibiarkan bangkrut, maka zona Eropa akan bubar dan perekonomian dilanda resesi. Yang akan menjalar ke seluruh dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak pakar telah menulis tentang ini. Salah satunya, Martin Feldstein, ekonom Harvard dan National Bureau of Economic Research, November lalu. Feldstein berpendapat bahwa kekacauan yang sedang berlangsung di Eropa saat ini bukanlah kecelakaan atau akibat salah-­‐urus; ia adalah konsekuensi logis dari sebuah eksperimen politik untuk menyatukan – tepatnya memaksakan bersatunya – ekonomi-­‐ekonomi dengan heterogenitas tinggi ke dalam sebuah mata uang tunggal. Perbedaan bukan hanya pada struktur ekonomi, tapi juga tradisi fiskal dan perilaku sosial. Menyatukan mereka berarti menyerahkan perbedaan kepada kebijakan moneter yang sama, tingkat bunga dasar yang sama serta kurs yang sama terhadap mata uang lain. Maka sekalipun salah satu negara anggota dapat meraih keuntungan atas negara non-­‐anggota melalui perubahan harga relatif, ia tidak dapat merealisasikannya, karena terikat pada kurs mata uang bersama. Dalam sistem yang fleksibel, sebuah negara yang mengalami penurunan permintaan agregat bisa menurunkan tingkat bunga untuk memotivasi perekonomian. Namun sistem mata uang tunggal juga menghalangi ini. Akibatnya, tingkat bunga menjadi relatif terlalu tinggi di negara yang mengalami pengangguran meningkat dan terlalu rendah di negara yang mengalami kenaikan upah. Distorsi-­‐distorsi inilah yang lalu mengaburkan fungsi harga dan tingkat bunga sebagai pembawa pesan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam perekonomian negara-­‐negara anggota. Dan sekarang ia meledak. Feldstein bahkan sudah mengingatkan risiko 1 Tulisan in dimuat di majalah TEMPO, 12 Desember 2011 2 Direktur LPEM-­‐FEUI ini pada tahun 1992 di majalah The Economist, tujuh tahun sebelum uang tunggal berlaku resmi di Eropa. Lantas, apa akibatnya bagi kita? Sekalipun kaitan ekonomi kita masih kecil, namun ambruknya ekonomi Eropa dapat menjalar ke Indonesia melalui mitra dagang bersama, seperti Cina, Amerika Serikat, dan Jepang. Hingga Oktober, Cina merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar, yaitu sekitar 13% dari total ekspor Januari-­‐Oktober 2011; disusul Jepang (11%) and Amerika Serikat (10%). Sementara itu, Cina, Amerika Serikat, dan Jepang mengirim 17%, 20%, dan 12% dari total ekspor mereka masing-­‐masing ke Eropa. Maka, jika permintaan Eropa ke ketiga negara tersebut menurun drastis tahun depan, besar kemungkinan Indonesia juga akan mengalami dampaknya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, lewat jalur perdagangan. Guncangan di Eropa juga dapat masuk ke Indonesia melalui jalur keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008/2009, misalnya berupa terbatasnya akses kepada sumber pembiayaan internasional serta tekanan pada kurs rupiah. Juga dapat terjadi penipisan likuiditas karena informasi tentang risiko krisis atau resesi menimbulkan perilaku latah yang lalu menyebabkan orang-­‐orang mengalihkan asetnya ke tempat-­‐tempat yang dipandang lebih aman, walau dengan imbal lebih rendah (safe haven). Jika ini terjadi masif, sektor perbankan menjadi terancam. Di sini isunya jadi lebih kompleks. Misalnya, upaya menekan bunga rendah untuk merangsang perekonomian berpotensi inflatoir dan mendorong modal keluar. Sebaliknya, mempertahankan bunga terlalu tinggi akan menekan insentif di sektor riil dan memperbesar risiko arus modal masuk jangka pendek, yang lalu mengganggu kestabilan makro lewat volatilitas kurs. Betul, bahwa ekonomi Indonesia masih menunjukkan tren yang baik. Bahkan dibandingkan dengan negara-­‐negara industri yang sekarang dililit masalah, Indonesia tampil kontras – misalnya dilihat dari rasio utang terhadap PDB (di bawah 30%, dibandingkan misalnya dengan Yunani 110%, Jepang 200%, dan Jerman 80%) atau defisit publik (di bawah 3%, dibandingkan Yunani yang lebih dari 10% pada tahun 2010). Indikator lain juga menunjukkan perbaikan tahun 2011 ini, dengan pertumbuhan kuartal ketiga mencapai 6,5% -­‐ sebagaimana dua kuartal sebelumnya. Sektor manufaktur kembali bangkit, tumbuh 6,6% pada kuartal ketiga. Yang mengejutkan adalah tumbuhnya kembali tekstil, pakaian, dan alas kaki sebesar rata-­‐rata 9% pada paruh pertama 2011, sangat kontras dengan hanya 1% pada tahun sebelumnya (Manning dan Purnagunawan 2011). Pertumbuhan ekspor juga meningkat menjadi 18,5% pada kuartal ketiga. Dengan impor yang sedikit melambat, ekspor bersih tumbuh sebesar 34% pada kuartal ketiga. Investasi mengalami penurunan menjadi 7% di kuartal ketiga, dari 9% kuartal sebelumnya -­‐ namun demikian, peranannya dalam pertumbuhan PDB masih di atas 30%. Tetapi, fakta bahwa Indonesia cukup bisa bertahan dari hempasan eksternal di tahun 2008 dan bahwa pasar domestik Indonesia cukup besar bukan berarti Indonesia sebaiknya semakin berfokus pada pasar dalam negeri. Dengan semakin dinamisnya jaringan produksi regional maupun global, kurang bijaksana jika Indonesia menafikan kesempatan memanfaatkan potensi pasar eksternal. Asia Timur adalah wilayah paling dinamis saat ini. Bahkan diharapkan, perekonomian dunia tahun-­‐tahun mendatang justru diselamatkan oleh pertumbuhan di negara-­‐negara berkembang, terutama di Asia Timur (World Economic Outlook 2011). Karena itu, kebijakan peningkatan infrastruktur maupun perbaikan sistem logistik tetap diperlukan, bukan hanya untuk tujuan konektivitas dalam negeri, tapi juga untuk memperlancar arus barang dan jasa internasional. Tentu ini tidak mudah. Yang cukup menguatirkan adalah semakin turunnya daya saing Indonesia. Dalam dua tahun belakangan peringkat Indonesia dalam laporan Doing Business dari World Bank dan International Finance Corporation terus turun dari 122 tahun 2010 menjadi 126 dan 129 pada 2011 dan 2012. Walaupun terjadi perbaikan dalam prosedur memulai usaha di Indonesia, ukuran lain seperti akses kredit, akses listrik, serta administrasi properti malah menurun. Sementara itu, Global Competitiveness Report 2011-­2012 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia di urutan 46 dari 142 negara yang disurvei. Pada laporan sebelumnya Indonesia berada di urutan 44 dari 139 negara yang disurvei. Menurut laporan ini, masalah utama berbisnis di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah, serta tidak memadainya infrastruktur. Kita tidak asing dengan isu-­‐isu ini. Dalam survei iklim investasi putaran kelima (Juni-­‐Desember 2010), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-­‐FEUI 2011) menemukan bahwa ketidakstabilan makroekonomi, ketersediaan listrik, dan akses transportasi masih tetap menjadi faktor utama dalam pertimbangan bisnis perusahan-­‐ perusaan manufaktur dan jasa di Indonesia. Survei tersebut melibatkan lebih dari 450 perusahaan manufaktur dan hampir 300 perusahaan jasa di 6 kota besar di Indonesia. Survei ini juga menemukan bahwa dampak negatif dari krisis global 2008/2009 lebih terasa di sektor manufaktur (misalnya perusahaan-­‐ perusahan yang bergerak dalam usaha kayu, bambu, dan rotan) ketimbang sektor jasa. Sebagian besar perusahaan ini terlibat dalam aktivitas ekspor-­‐impor, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif krisis menimpa mereka melalui permintaan yang berkurang, pasokan bahan baku yang lebih susah, ataupun karena volatilitas nilai tukar dan aliran modal jangka pendek. Maka kita memasuki 2012 dengan harap-­‐harap cemas. Indikator makro terakhir menunjukkan tren yang baik. Namun kita tidak boleh lengah. Seperti kejadian 2008, ada senjang waktu sebelum dampak krisis global mencapai Indonesia. Sementara itu, pekerjaaan rumah tetap menunggu penyelesaian. Terlepas dari krisis Asia, krisis global, dan sekarang krisis Eropa, kendala utama sisi penawaran ekonomi Indonesia adalah kondisi infrastruktur. Infrastruktur kasar berkaitan terutama dengan transportasi dan listrik; dan infrastruktur lunak terutama birokrasi yang efisien. Ini termasuk isu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Satu contoh tidak sinkronnya kebijakan daerah dan pusat adalah tetap dipungutnya biaya untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sekalipun telah dinyatakan bebas biaya melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Di luar, citra Indonesia cukup bagus. Postur internasional seperti anggota G20, Ketua ASEAN 2011, dan Ketua APEC 2013 mungkin membanggakan. Namun di saat lain, urusan domestik tetap banyak, bahkan semakin bertumpuk. Semoga 2012 adalah tahun di mana kita bisa menahan dampak krisis Eropa, sembari memperbaiki diri. ***