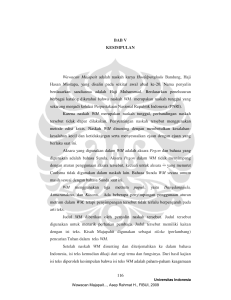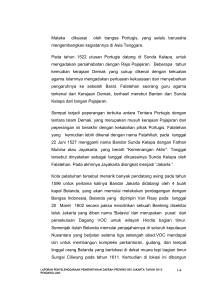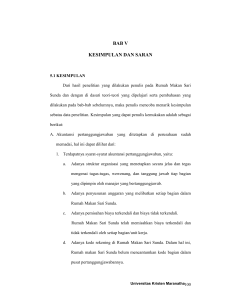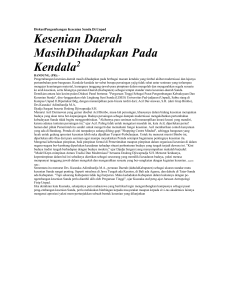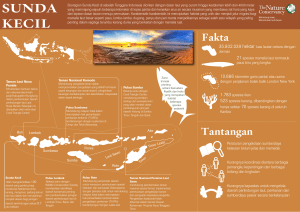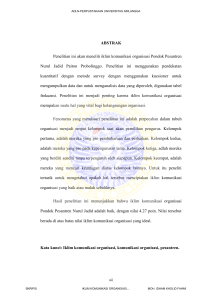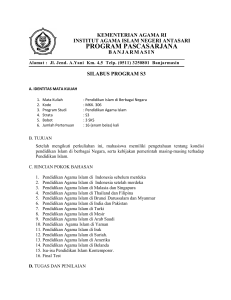K.H. Mustapa: Jejak Akhir Relasi Budaya Lokal dan Pesantren
advertisement

K.H. Mustapa: Jejak Akhir Relasi Budaya Lokal dan Pesantren Oleh: Ahmad Gibson al-Bustomi “Baheula ku basa Sunda ahirna ku basa Arab; jadi kaula nyundakeun Arab nguyang ka Arab, ngarabkeun Sunda tina Basa Arab” (Hasan Mustapa, Qur’anul Adhimi) Relasi kebudayaan Sunda dan Islam telah cukup lama menjadi pembicaraan, khususnya dari kalangan akademisi, baik dari sisi histroris maupun kajian budaya. Keakraban antara dunia pesantren dengan kebudayaan Sunda, diantaranya ditandai oleh banyaknya nadoman dan pupujian yang menggunakan bahasa Sunda dan biasa dilantunkan di pesantren atau majelis taklim di mesjid-mesjid. Demikian juga sebaliknya, tidak sedikit dangding atau tembang Sunda yang bertemakan keagamaan, Islam. Unsur-unsur kebudayaan memang sangat beragam, bukan hanya bidang seni belaka, akan tetapi keberadaan seni paling tidak bisa dijadikan indikator yang lebih bisa diukur berkenaan dengan relasi antara sub-kultur pesantren dengan kebudayaan lokal di mana pesantren itu berada. Diantara sejumlah karya seni yang mengindikasikan adanya relasi antara tradisi pesantren dengan tradisi lokal Sunda, dalam kadar yang cukup “kental” adalah karya-karya dangding K.H. Hasan Mustapa (HHM). Tokoh yang kedua kakinya secara sangat kokoh menapak di kedua wilayah tersebut (tradisi pesantren-Islam, dan kebudayaan lokal Sunda). Sosok K.H. Hasan Mustapa, baik sebagai tokoh agama (Kyai), maupun sebagai tokoh budaya berada di persimpangan, hadir sebagai sosok dari tokoh misterius. Sebagai bujangga, seperti dikatakan Hawe Setiawan, apa pun peran dan posisi HHM dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, yang jelas karya-karya (sastra)-nya sangat luar biasa, dan sangat sulit mencari tandingannya di tatar Sunda, sampai sekarang. Dengan kata lain, posisi HHM dalam khazanah sastra lokal Sunda tidak diragukan, juga tidak ada yang meragukannya, baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas. Siapa diantara budayawan Sunda (bahkan mungkin Nasional), yang memiliki produktivitas di atas 10.000 puisi (dangding)? Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kualitas karya sastranya. Karya sastra HHM yang dikategorikan sebagai sasta religius, belum termasuk sejumlah karya tulis keagamaan dalam bentuk esai, dan juga mengingat posisinya sebagai Penghulu Agama, tentunya HHM memliki posisi tersendiri dalam dinamika keagamaan pesantren, paling tidak di wilayah Bandung dan Priangan; oleh karenanya HHM dikenal dan dijuluki sebagai Kyai. Namun demikian, ada misteri besar berkenaan dengan “ketokohan” HHM, baik sebagai bujangga (sastrawan) maupun sebagai elite agama. Kebesaran nama dan karyanya tidak sebesar pengenalan masyarakat agama dan budayawan (sastrawan) lokal terhadap karyakarya besarnya. Misteri dari tidak populernya pemikiran dan ketokohan HHM dalam bidang pemikiran keagamaan di kalangan pesantren sebenarnya masih sangat bisa dimengerti. Karena, dalam wilayah pemikiran keagamaan HHM yang mengindikasikan faham sufistik (wujudiah) yang dengan tegas banyak ditolak oleh komuniatas pesantren dan komunitas agama lainnya, www.uinsgd.ac.id / artikel Page 1 khsusunya dari kalangan pembaharu. Lebih dari itu, karena tipologi keberagamaan masyarakat Sunda (dan umumnya Indonesia) adalah tipologi keberagamaan fiqhiyah; tipologi keberagamaan yang oleh HHM disebut tipologi keagamaan “nyembah nyabeulah“, maka sangat wajar bila pemikiran keagamaan HHM yang sarat dengan pemikiran sufistik tersebut tidak begitu akrab dengan kehidupan keagamaan masyarakatnya. Kalau pun ada diantara mereka yang cukup mengenalnya, paling tidak namanya dan diakui sebagai seorang Kyai, bisa dipastikan itu ada dari kalangan tua, dan itu pun dari komunitas yang menganut faham keagamaan (pesantren) tradisonal dan mempraktekkan amalan sufistik, thariqat. Lalu bagaimana dari kalangan budayawan? Sejauh mana sebenarnya budayawan (lokal) Sunda mengenal HHM sebagai bujangga? Atau, seberapa sering dan komunitas budaya lokal Sunda mana yang sering mementaskan karya-karya besar HHM? Kalau ada, dangding yang mana yang biasa dan sering dipentaskan? Rasanya sangat langka untuk tidak mengatakan bahwa tidak pernah ada komunitas budaya lokal yang pernah dan biasa mementaskan karyakarya besar HHM. Kecuali di kalangan yang sangat terbatas dan memang secara spesifik membicarakan dan mengupas tentang karya dan ketokohan HHM, yang hal itu pun masih sangat jarang dilakukan. Bahkan, tidak pula menjadi salah satu pokok bahasan dalam materi pengajaran Bahasa Sunda dan kebudayaan Sunda di sekolah-sekolah tatar Sunda. Konon, kesulitan terbesar dari kalangan budayawan dalam mengapresiasi karya-karya HHM adalah justru karena sarat dengan pemikiran dan petuah yang bersifat religus (sufistik) yang sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti. Asumsi dan argumen ini secara tidak langsung mengindikasikan renggangnya relasi budaya lokal dengan pesantren serta terjadinya proses pewarisan budaya di kalangan komunitas budaya yang tidak lengkap, yang hanya mengedepankan aspek permukaan (artistik) dari karya-karya budaya pendahulunya, dan mengenyampingkan makna-makna serta “piwuruk” yang terkandung dalam karya-karya mereka. Karya-karya HHM bila kita simak merupakan salah satu jembatan besar yang menghubungkan tradisi pemikiran pesantren dengan kebudayaan lokal Sunda. Namun, ketika karya-karya HHM tersebut telah sekian lama, sampai kini, tidak cukup dikenal dan tidak disentuh oleh kedua belah pihak, maka kita harus menyebutkan bahwa karya HHM telah menjadi prasasti dari jejak akhir relasi budaya lokal Sunda dan Pesantren. Jejak awalnya konon telah sejak awal ditanamkan secara kuat oleh pioner penyebar Islam di tatar Sunda, yang telah melahirkan ragam budaya lokal yang sangat kaya dan monumental. Dengan demikian, dari sisi apa pun, HHM tak lebih dari sekedar tokoh legenda tatar Sunda, atau bahkan mungkin tak lebih dari tokoh mitologis. Keindahan karya dangding (puisi) HHM memang bukan terletak dalam penggunaan kata-kata yang “puitik”, akan tetapi pada keindahan dan kepiawaian dalam penggunaan logikanya. Hawe menyebutnya dalam ungkapan-ungkapan paradoks yang sering digunakan HHM yang membuat karya puisi HHM demikian luar biasa, disamping kepiawaiannya dalam menciptakan diksi-diksi baru. Diksi-diksi yang diambil dari term dan bahasa Arab (atau lebih tepatnya term keagamaan, Islam) yang menjadi bagian dari “tradisi” kepesantrenan dan dimodifikasi dan disesuaikan dengan pola pelapalan lidah masyarakat Sunda dan bahasa Sunda. Apa yang diupayakan HHM dalam menjembatani tradisi lokal dan tradisi pesantren sebagai icon bagi tradisi keagamaan dan pemikiran Islam, dari sisi “pemikiran” secara substansial www.uinsgd.ac.id / artikel Page 2 telah berhasil. HHM mampu meramu dan mendialogkan kedua sistem nilai tersebut dengan cara apa yang HHM katakan : “Baheula ku basa Sunda ahirna ku basa Arab; jadi kaula nyundakeun Arab nguyang ka Arab, ngarabkeun Sunda tina Basa Arab“. Namun, secara sosio-kultural telah gagal. Jangankan menjembatani kedua “komunitas” tersebut, bahkan namnya sendiri semakin lama semakin tenggelam dari sejarah ingatan masyarakat Sunda, baik kalangan pesantren maupun budayawannya. Atau jangan-jangan masyarakat Sunda dan komunitas Pesantren di tatar Sunda sendiri yang tidak berhasil, bahkan tidak perduli dengan adanya upaya “rekonsiliasi” serta upaya dalam menjembatani antara budaya lokal Sunda dengan tradisi pesantren? Sehingga apa yang HHM lakukan pun tidak pernah mendapatkan perhatian dan sambutan yang layak, dan dianggap angin lalu? Sejumlah komunitas maupun perseorangan telah ada yang secara serius mengungkap dan mensosialisasikan karya-karya HHM. Namun, sampai sekarang, alih-alih dijadikan sebagai “media” yang menyambungkan kembali relasi pesantren dengan budaya lokal Sunda, bahkan untuk sekedar mengangkat dan menjadikan karya HHM sebagai karya yang layak untuk dipentaskan dan mendapat apresiasi publik pun belum bisa disebut berhasil. Belum berhasil, akan tetapi tentu bukan berarti tidak berhasil, karena mungkin upaya yang dilakukan masih pada tahap pengenalan ulang terhadap karya besarnya. Hal ini bisa dimaklumi karena memang karya-karya HHM bukan sekedar karya seni “pintonan panglipur lara“, akan tetapi karya yang sarat dengan “pangwuruk” dan “penyintreuk” yang tidak bisa dinikmati, disimak dan disajikan (dipintonkan) secara sambi lalu. Penulis: Dosen Filafat Agama, Prodi Akidah dan Filsafat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Edisi/versi HU. Kompas (FORUM BUDAYA; Sabtu, 28 Maret 2009 | 11:27 WIB) www.uinsgd.ac.id / artikel Page 3