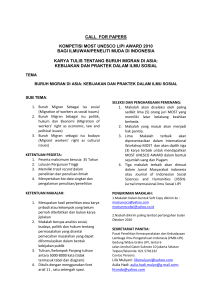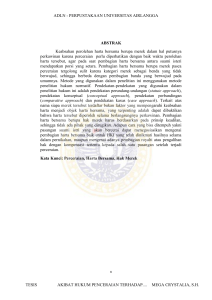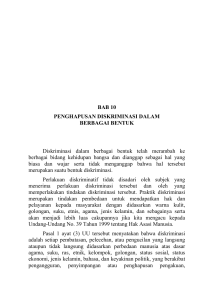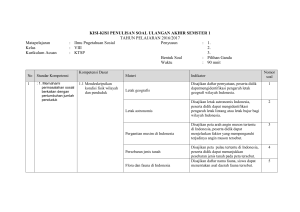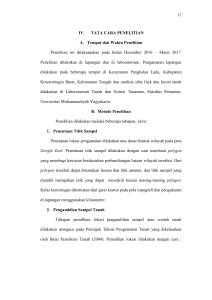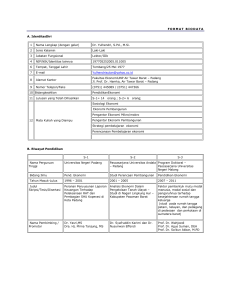volume i - APSSI Sosiologi
advertisement

Volume I i ii VOLUME I Prosiding KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Padang 18 – 19 MEI 2016 GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA Tim Editor: Jendrius (Universitas Andalas) Emy Susanti (Universitas Airlangga) Ida Ruwaida (Universitas Indonesia) Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret) Herlan (Universitas Tanjung Pura) Azwar (Universitas Andalas) e-ISBN: ISBN: 978-602-99467-03 978-602-99467-1-0 (jil. 1) Kerjasama: APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas Diterbitkan Oleh: Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas 2016 iii KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa dan berlangsung dari tgl 18 – 19 Mei 2016 ini, melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut. Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni (BAB I –BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri dari 10 BAB (BAB VIII – BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda, keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya. Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkuslumus dalam membantu pelaksaan Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Padang, 18 Mei 2016 Tim Editor iv DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi VOLUME I I. GERAKAN PEREMPUAN 1. Wahidah Rumondang Bulan Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan? 2. Kustini Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim Di Indonesia 3. Yunindyawati Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga 4. Ida Ruwaida Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan 5. Novita Saseria Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat 6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara 7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan 8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa 9. Syafruddin Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan Di Suku Sasak Lombok 10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, JarotSantoso, Tri Sugiarto, Joko Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati …………… Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang Di Tengan Monetisasi Perdesaan. 11. Rizki Takriyanti Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan 12. Shirley Goni Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara 13. Selinaswati Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak Ranperda Diskriminatif: StudiKasus Gerakan FKWIS Sumatera Barat tahun 2001 14. Indraddin ……………….……………………...………… ….. Gerakan Masyarakat Lokal Mengelola Remitance untuk Pengentasan i ii 1 31 39 58 71 99 113 126 137 152 167 195 202 215 v Kemiskinan 15. Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati………………………………… Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten II. GERAKAN AGRARIA 1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi: Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII di Ogan Ilir 2. Ferdinal Asnim Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik 3. Herlan Kerawanan Konflik Sosial Pembanginan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat 4. Siti Aminah Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat 5. Amruddin Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis 6. Sityi Maesarotul Qori’ah Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 7. Iskandar Dzulkarnain Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura: Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol 8.Caritas Woro Murdiati Runggandini Renegosisasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma dalam Pengelolaan Hutan. 9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor ............................................. Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi Perlawanan Orang Akit di Riau III. GERAKAN BURUH 1. Rio Tutri ..................................................................................... Jerat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam Melihat Gerakan Buruh 2. Anggreni Primawati ................................................................... Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia Di Malaysia 3. Sigit Rochadi .............................................................................. Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 4. Yoyok Hendarso ......................................................................... Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak, Malaysia 5. Yogaprasta Adi Nugraha .......................................................... 231 254 266 280 292 303 313 329 336 356 372 388 400 418 448 vi Melawan Tembok Besi Tuan tanah: Sebuah Realitas Ketidakberdayaan Buruh Tani Melawan Hegemoni Alat Panen di Sulawesi Selatan 6. Ikhsan Muharma Putra Gerakan Kelompok Miskin dan Marginal pada Konteks Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 7. Indhar Wahyu Wira Harjo, Yogi Eka Chalid Farobi Konstelasi Media Massa Lokal dalam Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel Rayja 461 477 IV. GERAKAN LINGKUNGAN 1. Damsar, Indrayani ..................................................................... 490 Pasar Loak: Gerakan Lingkungan Global 2. Victoria Sundari Handoko ........................................................ . 500 Komodifikai Desa Wisata: Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata di Bejiharjo, Gunung Kidul 3. Siti Zunariyah, Akhmad Ramdon .......................................... 512 Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang Berwawasan Lingkungan 4. Rachmad K. Dwi Susilo ............................................................ 528 Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Identitas Kolektif dalam Gerakan Sosial untuk Konservasi Sumber Air 5. Irsadi Aristora ........................................................................... 538 Melawan Asap Sebagai Hak Dasar Manusia 6. Tri Agus Susanto, Vieronica Varbi Sunundiati, Diana Dewi Sartika .555 Gerakan Masyarakat Pasang Surut Melestarikan Sungai: Analisis Struktur, Kesempatan Politik, mobilisasi dan Perubahan Sosial 7. Bintarsih Sekarningrum, Yusar .............................................. 568 Perilaku Komunitas dalam Gerakan Pungut Sampah (GPS) di Kota Bandung 8. Lina Marina Rohman ............................................................... 577 Gerakan Rakyat Melawan Proses Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 9. Lutfi Amiruddin ........................................................................ 600 Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel di Sekitar Sumber Mata Air 10. Rusfadia Saktiyanti Jahya .................................................... 611 Gerakan Lingkungan Penyadaran UKM Untuk Pembangunan Berkelanjutan 11. Sulistyaningsih ........................................................................ 621 Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. 12. Bernardus Wibowo Suliantoro ............................................. 638 Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Hutan Berperspektif Gender Berbasis Kearifan Lokal. 13. Royke R. Siahainenia .............................................................. 646 Ruang Publik Virtual sebagai saluran Perlawanan terhadap Kapitalisme Pertambangan vii 14. Miswanto ........................................................................... 671 Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang 15. Akhmad Ramdon, Kusumaningdyah, Siti Zunariyah ........ 685 Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas untuk Merawat Kembali Kampung, Sungai dan Kota 16. Vieronica Varbi Sununiati ......................................... 699 Diet Kantong Plastik di Kota Palembang 17. Yogi Suprayogi Sugandhi, Rini Susetyawati Soemarwoto, Mila Mardotillah ................................................................................. 717 Gerakan Sosial Melalui Rumah Sehat dan Imunisasi BCG sebagai Langkah Menurunkan Kejadian TB di Padang 18. Evelin J.R. Kawung 729 Kaji Tindak Konsep Pembagian Kerja Antara Aparat dengan Masyarakat dalam Program Berbasis Lingkungan ; Studi Kasus Kelurahan Malalayang Satu Timur Kota Manado V. GERAKAN PETANI DAN NELAYAN 1. Zaiyardam Zubir, Lindayanti, Fajri Rahman ...................... 740 Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani Riau Masa Orde Baru dan Reformasi 1970 - 2010 2. Iwan Nurhadi ............................................................................. 761 Habitus Petani dan Gagalnya Gerakan Sosial di Arena Perebutan Ruang Hidup 3. Suparman Abdullah .......................................................... 772 Diskontinyuitas Komunitas Nelayan: Kasus Lae-lae dan Kampung Nelayan, Kel. Untia, Makasar 4. Desi Yunita, Wahju Gunawan ................................................. 788 Perubahan Struktur Sosial dalam Masyarakat Petani Plasma Kelapa Sawit. 5. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisukmo, Herry Pramono ............................................................................ 810 Transformasi Sosial Komunitas Miskin di Kota Jakarta. 6. Hartoyo ............................................................................... 827 Perubahan Struktur Peluang Politik dan Strategi Adaptasi Gerakan Petani 7. Bob Alfiandi, Izar Ul-Haq ................................................ 842 Gejala Involusi Gerakan Petani Organik: Kasus Pada Komunitas Petani Alam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 8. Dewi Anggraini 860 Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan 300 KK Petani VI. KELOMPOK MINORITAS DAN MARGINAL 1.Elizabeth Imma Indra Dewi Windajani, Victoria Sundari Handoko, Gregorius Widiartana ................................................................. 881 Gerakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Melalui Pembentukan Kebijakan di Kabupaten Klaten viii 2. Cici Darmayanti 898 LGBT Identity Of Implimentation Islamic Shari’a In Aceh 3. Victoria Sundari Handoko 919 Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Bejiharjo, Gunungkidul 4. Rinaldi ................................................................................. 930 Representasi Gerakan LGBT dalam Media Massa: Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan LGBT dalam Pemberitaan Media Online 5. Ilham Havifi .......................................................................... 937 Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda Dalam Berprilaku 6. R.A. Tachya Muhammad, M.Fadhil Nurdin, Budi Sutrisno 968 Gerakan Sosial LGBT di Indonesia: Sejarah dan Tahapannya 7. Fifin Triswanti, Bangun Sentosa D. Haryanto ....................... 982 Menguak Eksistensi Minoritas Hindu Di Antara Agama Mayoritas Dalam Bingkai Tindakan Sosial Max Weber 8. Wahyu Pramono, Dwiyanti Hanandini 988 Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Mempertahankan Eksistensinya Dalam Sistem Ekonomi Kota 9. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisuksmo, Herry Pramono 1002 Transformasi Sosial Komunitas Miskin Kota Jakarta VII. GERAKAN POLITIK 1. Wirdanengsih ........................................................................ Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Partisipasi Politik Yang Cerdas 2.Sutrisno ...................................................................................... Relasi Kuasa Organisasi Sipil dengan Polisi Pasca 2000 3. Virtous Setyaka .................................................................... Relevansi Gerakan Sosial untuk Memperkuat Daya Saing Indonesia Dalam Masyarakat ASEAN 4. Al Rafni, Suryanef .................................................. Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif 5. Robertus Robet ............................................................ Anti Intelektualisme dan Terbenamnya Gerakan Sosial 6. Andri Rusta, Putri Gemala ............................................... Akuntabilitas Masyarakat Kota Padang Terhadap Pemilu Legislatif 2014 7. Asrinaldi .......................................................................... Politik Kekuasaan Penghulu dalam Praktik Demokrasi di Sumatera Barat 1020 1030 1052 1071 1086 1092 1119 ix BAB I GERAKAN PEREMPUAN x FENOMENA PENINGKATAN CERAI GUGAT = INDIKASI KEBANGKITAN PEREMPUAN? Wahidah Rumondang Bulan Komunikasi, FISIP, UPN “Veteran” Jakarta [email protected] Abstrak Peningkatan kasus cerai gugat di banyak daerah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (Badilag MA, 2014) menarik didalami mengingat dalam kasus perceraian, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang tersub-ordinasi (Gulardi dalam Ihromi, 1999; dan Nany Razak, 1980 dalam Fachrina, 2005). Apakah fenomena peningkatan kasus cerai gugat tersebut mengindikasikan kebangkitan perempuan? Dengan tujuan menemukenali alasan perempuan melakukan cerai gugat, dampak cerai gugat pada keluarga, serta respon struktur terhadap cerai gugat; studi kualitatif yang dilaksanakan pada April 2015 di Kota Padang ini juga mengelaborasi peran adat Minangkabau dalam cerai gugat karena budaya Minang dinilai menempatkan perempuan dalam posisi lebih berdaya. Hasil studi menunjukkan, meski perempuan melakukan cerai gugat, alasan tindakan lebih sebagai tindakan responsif ketimbang purposif, yaitu untuk memperjelas status pernikahan. Temuan lain, perempuan maupun laki-laki pada tiga pasangan muda yang diteliti cenderung lebih rasional baik karena faktor pendidikan maupun karena intervensi informasi dari media massa. Toleransi tiga pasangan tersebut terhadap kondisi yang tak diinginkan cenderung rendah yang mengindikasikan menurunnya ketahanan keluarga. Terkait peran adat, adat Minangkabau tidak menstimuli cerai gugat namun membantu perempuan mantap atas keputusannya melalui dukungan keluarga luas. Meskipun mulai memudar, peran keluarga luas dalam pernikahan tetap eksis dengan keterlibatan para pihak yang makin terbatas dan dengan kadar dukungan yang makin rendah (formalnormatif). Keyword: cerai gugat, keluaga luas, ketahanan keluarga, tindakan responsif, tindakan purposif. Abstract The increasing number of petitions of divorce by women in many regions in Indonesia in the last decade (Badilag MA, 2014) interesting to elaborate because in case of divorce women often placed in sub-ordination position (Gulardi in Ihromi, 1999; and Nany Razak, 1980 in Fachrina, 2005). Are these indications the revival of women? With the aim to understand why women propose the divorce, the impact of divorce for family, and the structural response to the divorce by women; studied that held in April 2015 in the city of Padang also intended to elaborate the role of indigenous Minangkabau in cases of divorce by women because culture of Minangkabau assumed to place women in more equal social position. The results of the study showed that although women took initiative to divorce, the reason of action is more as responsive action rather than purposive action, namely to clarify the status of marriage. Other findings, both women and men on three pairs of young families that studied tend more rational because of their education beside the information from the media; their tolerance toward unwanted conditions generally low; and there are indications of declining of family resilience in young couples (more subjective and not substantive). Related with the role of indigenous Minangkabau, custom do not stimulate the divorce but help women convinced with their action through extended family support. Although it began to fade, role of extended family still exist in Padang City 11 but the parties that involved more limited and the level of involvement getting lower (formality or normative orientation). Keyword: divorced by women, indigenous of Minangkabau, extended family, family resilience, purposive action, responsive action. I. PENDAHULUAN Ada yang menarik dari data yang dilansir Badan Pengadilan Agama (Badilag MARI) tahun 2010- 2014. Selain terjadi peningkatan angka perceraian, angka cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri diberbagai daerah di Indonesia juga mengalami tren naik, bahkan dengan jumlah angka melampaui cerai talak (gambar 1 dan 2). Perbandingan Cerai Talak & Cerai Gugat Cerai Talak Cerai Gugat 268,381 250,360 169,673 81,535 2010 191,013 85,779 2011 212,595 91,800 2012 111,456 113,850 2013 2014 Gambar 1: Data Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014 Prosentase Perbandingan Th 2014 Cerai Talak 30% Cerai Gugat 70% Gambar 2: Prosentase Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2014 Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014 12 Apa yang menjadi penyebab? Kementerian Agama selaku kementerian yang sebelumnya bertanggung-jawab menangani kasus-kasus perceraian melalui institusi strukturalnya (Kantor Urusan Agama atau KUA dan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau BP4), menduga hal itu karena perubahan kebijakan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No 3 Tahun 2006. Di dalam aturan tersebut penyelesaian perselisihan suami-isteri (proses perceraian) kini tidak lagi melibatkan KUA dan BP4, akan tetapi sepenuhnya ditangani Pengadilan Agama yang sudah tidak berada di bawah Kementerian Agama. Penyelesaian permasalahan “ala” pengadilan inilah yang ditengarai menyebabkan banyak kasus perselisihan rumah tangga berakhir dengan perceraian termasuk cerai gugat, dan yang memicu pelonjakan jumlah kasus perceraian. Dugaan lain terkait dengan kesadaran gender perempuan yang makin baik, yang sejak lama disebut-sebut sebagai pemicu. Hal itu juga diungkap George Levinger dalam Rodliyah (2011), yang mengatakan bahwa perceraian dapat disebabkan karena adanya pandangan tentang etos persamaan derajat dan tuntutan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ia juga mengungkapkan bahwa pandangan perempuan yang makin luas dapat melahirkan berbagai alternatif pilihan bagi perempuan apabila bercerai. Dalam konteks itu pula peningkatan independensi perempuan mengingat pendidikan serta kemampuan mereka memenuhi kebutuhan ekonomi yang makin baik, juga dianggap menjadi penyebab. Di Australia misalnya, peningkatan kesempatan perempuan mencapai kemandirian finansial terbukti menjadi faktor penentu terjadinya peningkatan perceraian yang diinisiasi perempuan, selain karena faktor peningkatan dana jaring pengaman sosial untuk keluarga rentan finansial (termasuk keluarga bercerai) dan melemahnya stigma sosial yang melekat pada perceraian (Qu & Soriano, 2004). Realitas serupa juga terjadi di Indonesia, sebagaimana studi Rodliyah (2011) yang menunjukkan bahwa terjadi tren baru peningkatan perceraian di Indonesia. Jika sebelumnya perceraian banyak menimpa pasangan dengan pendidikan rendah, kini justru banyak terjadi pada pasangan dengan pendidikan tinggi dengan cerai gugat sebagai kasus terbanyak. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Maret, 2016) mengamini hal tersebut dengan mengatakan bahwa berdasarkan riset terkait dikementeriannya, masalah utama retaknya hubungan suami istri di Indonesia umumnya terjadi karena istri memiliki pendapatan sendiri. Bagaimana dengan kondisi di Kota Padang tempat dimana studi dilakukan? Menarik menyimak catatan kecil Fathur Rizqi yang mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang selama sepuluh bulan mulai dari Mei 2011 hingga Maret 2012, semasa menjalani tugas sebagai calon hakim. Ia mendapati bahwa kebanyakan perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang terjadi pada pasangan dengan usia pernikahan yang relatif muda, yaitu kurang dari 10 tahun, dengan rata-rata usia pasangan yang bercerai berkisar di bawah 45 tahun (untuk laki-laki) dan 40 tahun (untuk perempuan). Tentang mengenai apa yang menjadi penyebab, sayangnya Fathur Rizqi tidak menyebutkan secara spesifik mengapa terjadi banyak kasus cerai gugat. Seperti halnya data umum yang terdapat di Pengadilan Kota Padang, perceraian di Kota Padang menurutnya yang dominan karena salah satu pasangan (umumnya suami) tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya (istri dan anak-anak) selain karena salah satu pasangan (umumnya istri) terlalu menuntut dan tidak bisa menghargai hasil usaha pasangannya (suami). Ia juga mencatat adanya kasus perceraian akibat orang ketiga, yang terjadi lebih karena suami-istri tinggal berjauhan serta karena perbedaan yang terlalu mencolok antara pihak suami dengan istri (pendidikan, usia, status ekonomi, kondisi fisik). Ia juga mencatat beberapa kasus perceraian yang terjadi karena permasalahan sepele, yang menjadi fatal 13 karena tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri ataupun pihak keluarga suami dan istri. Adanya campur tangan pihak keluarga yang berlebihan atau mendominasi, persoalan ketidak-jujuran antara suami dan istri dalam hal finansial (pemasukan maupun pengeluaran), buruknya komunikasi, perilaku yang buruk yang sudah dilakukan sejak sebelum menikah seperti berjudi, mabuk, suka main pukul, dan terjerat narkoba; menjadi penyebab lainnya mengapa perceraian banyak terjadi dalam kasus-kasus yang diikutinya. Dalam konteks itulah studi ini dilakukan, yaitu mendalami alasan-alasan pihak istri mengenai mengapa mereka memutuskan melakukan cerai gugat, guna melihat apakah keputusan subjektif perempuan tersebut berkorelasi dengan isu-isu kesetaraan gender seperti yang telah dijelaskan. Selain itu, mengingat meski secara legal-formal diperbolehkan (agama maupun hukum positif) namun secara normatif perceraian terlebih lagi cerai gugat masih dinilai sebagai tindakan negatif (Fachrina, 2006); bagaimana fenomena cerai gugat dapat meningkat di Padang sementara masyarakat Minang dinilai masih kuat berpegang pada nilai-nilai transsendental. Yang tidak kalah penting, mengingat keberadaaan adat Minangkabau dengan budaya matrilineal yang khas (terutama bagi kehidupan perempuan), studi juga dilakukan untuk melihat bagaimana adat berperan dalam kasus cerai gugat yang terjadi. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Normatif Cerai Gugat Cerai gugat merupakan salah satu bentuk perceraian yang diakui di dalam Islam, yang dikenal dengan istilah ‘khulu’, yaitu perceraian dengan tebusan atau imbalan dari istri kepada suami (QS-An-Nisa ayat 4, dan QS al-Baqarah ayat 229). Meski merupakan tindakan yang diperbolehkan, cerai gugat sebagaimana halnya cerai talak merupakan tindakan yang tidak dianjurkan (tindakan yang diperbolehkan tapi dibenci). Cerai gugat bahkan diidentifikasi lebih negatif, karena perempuan yang melakukannya dengan alasan tidak jelas terancam tidak akan mencium bau syurga (Hadist riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban). Sedangkan di dalam hukum positif cerai gugat diatur di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 20), yang menyatakan bahwa tindakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Cerai gugat juga disebut di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 2.2 Tinjauan Teoretis Cerai Gugat Merujuk Wong (1976), peningkatan fenomena cerai gugat secara teoretis sesungguhnya mengindikasikan terjadinya peningkatan keberanian perempuan mendobrak mitos yang ada. Mengapa? Karena sebagaimana diungkap Wong, ketika masih gadis, perempuan selalu menurut dan tergantung pada ayahnya. Ketika menikah, ia tergantung pada suaminya dan ketika menjadi janda sekalipun, ia tetap harus menurut dan tergantung pada anak laki-lakinya. Perempuan baru benar-benar bisa “berbicara” ketika ia menjadi mertua (Wong, 1976: 15). Lalu bagaimana peningkatan keberanian perempuan dapat terjadi? Menurut Levinger (1979) sebagaimana dikutip Rodliyah (2011), hal itu diantaranya karena: (1) Adanya perubahan pandangan tentang nilai dan norma perceraian, (2) Adanya pandangan tentang etos persamaan derajat dan tuntutan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, (3) Pandangan yang semakin luas dari pihak perempuan melahirkan berbagai alternatif pilihan apabila bercerai, (4). Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari 14 lingkungan keluarga atau kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggan terhadap ketahanan sebuah perkawinan, dan (5) karena kemandirian ekonomi pihak perempuan. Sedangkan mengenai bagaimana tindakan cerai gugat dapat terjadi, hal itu dapat dipahami melalui Stage Theory (Gambar 3 ). Gambar 3. Stage Theory (ABCD Theory), Levinger (1980). Sebuah hubungan menurut teori tersebut berlangsung dalam sejumlah tahapan, yaitu A-B-C-D-E. Tahap paling kritis terjadi ketika hubungan mengalami kerusakan (Deterioration), yaitu ketika hubungan telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi ketidak-seimbangan antara cost dengan reward. Ketika hubungan telah lebih banyak menimbulkan kerugian, pada tahap itulah kemungkinan keinginan untuk mengakhiri hubungan (Ending), termasuk dalam konteks cerai gugat, dapat terjadi. Lebih detail hal itu dapat dilihat pada Model of Rational Choice in Divorce yang dikembangkan Levinger berdasarkan Rational Choice Theory, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. Levinger's Model of Rational Choice in Divorce Attractions - Magnets = rewards that stem from being married Barriers () +/- Walls = punishments or losses you'd face if you divorced. You'd have to climb over these walls if you divorced. Alternative Attractions Lures Away From Your Marriage = something attractive that you could obtain if you were unmarried. Positive Social Status Loss of positive status and gain of new negative-status stigma of being divorced Liberated status with freedom to explore relationships with others Wealth Accumulation Division of wealth (at least by half) Opportunity to be disentangled from family costs Co-parenting Co-parenting with ex-spouse -never truly free from this role Shared custody, alleviating some degree of burden of parenting Sex Much less availability and predictability of sexual partner Possibility of new sexual partner 15 Health Support and Stress Buffer Loss of health support and additional stress from divorce process Different types of stressors and relief from pre-divorce stresses Stay Married Formula ↑Attractions ↑Barriers ↓Lures Divorce Formula ↓Attractions ↓Barriers ↑Lures Gambar 4. Model Levinger Mengenai Rational Choice dalam Perceraian. (http://freesociologybooks.com/Sociology_Of_The_Family/12_Divorce_and_Separation. php) Terkait itu perlu pula ditampilkan teori Coleman tentang Rational Choice (Ritzer, 2007), yang gagasan dasarnya mengungkapkan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (serta tindakannya) ditentukan oleh nilai atau pilihan/preferensinya (Coleman, 1990). Akan tetapi berbeda dengan Levinger yang cenderung melihat aktor bersikap kalkulatif atas hubungan yang terjalin, menurut Coleman tindakan aktor termasuk tindakan tidak rasional, karena menurut Coleman dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional. Ia mengatakan, “Asumsiku adalah bahwa ramalan teoretis yang dibuat disini sebenarnya akan sama saja apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan atau menyimpang dari cara-cara yang telah diamati.” Merujuk Coleman maka tindakan cerai gugat dapat dipahami dengan mempelajari apa yang menjadi tujuan tindakan cerai gugat, yang sangat ditentukan oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan yang ditetapkan pelaku cerai gugat atas tindakan; bukan hanya karena aspek rasional namun juga karena aspek tidak rasional. 2.3 Studi Cerai Gugat Terdapat sejumlah studi cerai gugat yang relevan untuk diulas. Pertama studi Fachrina (2006) bertajuk Pandangan Masyarakat mengenai Perceraian, Studi Kasus Cerai Gugat pada Masyarakat Perkotaan (termasuk Kota Padang), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memposisikan pihak istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi perceraian. Merujuk hasil studi tersebut penilaian masyarakat tentu akan menjadi lebih negatif terhadap cerai gugat, mengingat perceraian justru diinisiasi pihak wanita. Namun merujuk studi lanjutan yang dilakukan (2012), masyarakat ternyata cenderung mendua. Meski tidak setuju terhadap tindakan perceraian (termasuk cerai gugat), yaitu 73,3% tidaksetuju perceraian dan 80% menganggap perceraian harus dihindari, namun mereka bersikap ambigu jika perceraian terjadi pada teman/tetangga. Mayoritas bersikap biasa saja dan dapat menerima. Studi kedua adalah studi Nunung Rodliyah (2011) tentang Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi, Studi Kasus di Kota Bandar Lampung. Dalam studi disertasi tersebut Rodhiyah menemukan bahwa kesadaran gender kaum wanita (muslim) telah menimbulkan fenomena baru, yaitu jika sebelumnya perceraian lebih banyak terjadi pada mereka dengan tingkat pendidikan rendah, pada kasus yang ditelitinya justru terjadi pada pasangan Muslim berpendidikan tinggi dengan kecenderungan cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Kesadaran gender dimaksud adalah kesadaran hukum dan hak-hak perempuan. 16 Studi lainnya adalah studi tentang Kasus Cerai Gugat Suami Isteri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok, Sleman, Jogjakarta Tahun 2007-2009; yang dilakukan oleh Sun Choirul Ummah. Menurut Sun terdapat faktor internal dan faktor eksternal penyebab cerai gugat. Untuk faktor internal diantaranya terkait dengan persepsi terhadap kesetaraan gender dari pihak istri, sedangkan untuk faktor eksternal diantaranya karena campur tangan pihak ketiga baik orang tua maupun kerabat dekat. Studi lainnya dilakukan Nunung Susfita, berjudul Cerai Gugat di Kalangan Masyarakat Kota Mataram, Studi Kasus di Peradilan Agama Kelas 1A Mataram Tahun 2004-2005. Berdasarkan hasil studi Susfita penyebab terbanyak cerai gugat karena faktor ekonomi (40%), diikuti faktor akhlak (25%) dan faktor KDRT (10%). Mengingat lokus studi hal ini dapat dipahami, meski kondisi serupa belum tentu terjadi di Kota Padang. 3. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus (tiga kasus cerai gugat), dengan observasi dan wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Sebagai catatan mengingat usia kritis perkawinan berada pada rentang usia pernikahan 1-5 tahun masa perkawinan, kasus yang dipilih adalah kasus dengan usia pernikahan 1-5 tahun dan telah bercerai maksimal 3 tahun terakhir dengan pertimbangan bahwa informan masih cukup baik mengingat proses perceraian yang terjadi dan bahwa proses perceraian pada rentang waktu tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Sebagai key informan adalah pihak istri selaku pelaku cerai gugat, serta informan lainnya yaitu suami sebagai pasangan yang dicerai gugat, atau unsur keluarga dekat yang mendampingi proses cerai gugat (suami tidak dijadikan key informan mengingat dalam kasus cerai gugat umumnya keberadaan suami sulit untuk diketahui atau jika diketahui sulit untuk diajak berkomunikasi), tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat struktural pengadilan agama, serta pejabat Kankemenag Kota Padang termasuk pejabat KUA/penghulu. Selain itu juga dihimpun data pendukung baik dari literatur, dokumen, dan laporan dari institusi terkait, maupun pemberitaan media massa. Selain di Kota Padang, studi Litbang Kemenang yang dilakukan pada April 2015 ini juga dilakukan di beberapa daerah lainnya, namun khusus untuk Kota Padang juga didalami peran adat dalam fenomena cerai gugat yang terjadi. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum. Sebagaimana terjadi di hampir banyak daerah di seluruh Indonesia, terdapat trend peningkatan angka cerai gugat di Kota Padang dari tahun ke tahun (2008-2013), yaitu: Tabel 1 Kasus Perceraian di Kota Padang Tahun 2008 – 2013 TAHUN 2008 2009 2010 2011 JUMLAH PERKARA 771 728 851 851 CERAI TALAK Jumlah Prosentase 261 38 246 35 278 33 328 35 CERAI GUGAT Jumlah Prosentase 424 62 462 65 573 67 615 65 17 2012 1042 354 34 688 66 2013 1052 351 33 701 67 Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klas I A Padang, tahun 2008-2012 (data diolah) Mengenai apa yang menjadi penyebab, tak ditemukan data yang secara spesifik menyebut faktor terjadinya cerai gugat. Data yang tersedia hanya menyebut penyebab perceraian secara umum, yaitu tidak adanya keharmonisan dan tidak ada tanggung-jawab, sebagai penyebab utama mengingat selalu muncul dengan frekuensi tertinggi selama kurun waktu 2010-2014. Selain itu terdapat faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan cemburu serta krisis akhlak, poligami, dipenjara/dihukum, kekejaman jasmani cacat biologis, KDRT, dan penganiayaan yang muncul dengan frekuensi relatif rendah (tabel 2). Meski tidak terdapat data spesifik tentang penyebab cerai gugat, mengingat kasus cerai gugat cukup dominan terjadi, data tersebut dapat dijadikan sebagai informasi umum. Tabel 2 Penyebab Perceraian di Kota Padang Tahun 2010-2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Penyebab Perceraian 2010 2011 2012 2013 2014 Poligami Tidak Sehat 2 4 5 Krisis Akhlak 8 31 35 Cemburu 2 22 68 16 18 Ekonomi 72 126 42 39 Tidak Ada Tanggung-jawab 143 328 468 243 169 Kawin Dibawah Umur 3 Dihukum/Dipenjara 2 1 Cacat BIologis 3 KDRT Gangguan Pihak Ketiga 30 18 76 132 127 Tidak Ada Keharmonisan 301 322 304 548 693 Penganiayaan 2 Kekejaman Jasmani 2 31 18 Sumber: Pengadilan Agama Padang Tahun 2014 (data diolah). 4.2. Proses Mediasi. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang sebelum memutuskan kasus perceraian termasuk cerai gugat, dilakukan melalui proses mediasi yang berlangsung maksimal 40 hari. Untuk kasus cerai gugat, proses mediasi tidaklah mudah dilakukan mengingat dalam banyak kasus cerai gugat, pihak suami umumnya tidak datang sementara proses mediasi mensyaratkan kehadiran kedua-belah pihak. Karenanya proses mediasi untuk cerai gugat relatif sangat jarang terjadi, untuk tidak mengatakan tidak pernah dilakukan. Karena itu pula penyelesaian kasus cerai gugat relatif lebih cepat, dapat diselesai putus dalam waktu kurang dari satu bulan! 18 Proses mediasi sendiri ditangani tiga hakim, yang sejak tahun 2013 juga melibatkan 2 orang dari unsur non hakim, yang diambil dari hakim senior yang sudah pensiun. Proses mediasi sebagaimana diungkap Ali Amar SH, MHI selaku hakim mediator dari unsur non hakim, diawali dengan disidangkannya perkara yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas ke hakim mediator. Mengingat banyaknya kasus, rata-rata hakim mediator menangani 20 perkara setiap bulannya. Karena hal itu proses mediasi (umumnya untuk kasus cerai talak) tidak terlalu efektif, meski beberapa kasus dapat mencegah terjadinya perceraian. 4.3. Peran Adat. 1 Dalam adat Minangkabau, terdapat satu institusi yaitu qodhi atau penghulu, yang dijabat oleh mereka yang dinilai memiliki kepahaman yang baik tentang hukum Islam yang kepemimpinannya berjenjang mulai ditingkat kaum hingga ditingkat Nagari. Qodhi secara umum berperan sebagai tempat kembali bagi suatu kaum umtuk mendapatkan pertimbangan hukum dan karena hal itu pula qodhi kaum dan Nagari dalam praktek seharihari kini difungsikan sebagai P3N atau pembantu penghulu. Sebagaimana tergambar dalam falsafah Minang, rumah bakali, kampung batuo (rumah atau kaum pasti ada kepemimpinannya, begitu juga kampung atau Jorong pasti ada kepemimpinannya). Penyelesaian permasalahan dilakukan pertama-tama ditingkat kaum, jika tidak selesai baru dibawa ke tingkat jorong, dan jika tidak juga selesai di bawa Jorong, selanjutnya di bawa ke Nagari. Dalam penanganan berbagai masalah tersebut qodhi memegang peranan penting, yaitu mengurusi masalah perkawinan atau kehidupan berkeluarga. Sebagai contoh jika seorang perempuan suaminya tidak pulang ke rumah paling lama tiga hari, maka pihak ninik-mamak akan mengusut untuk mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Perempuan yang suaminya tidak pulang akan ditanyai, begitu juga pihak sumando atau keluarga suami. Jika ditemukan masalah, kedua belah pihak akan menerima nasehat dari ninik-mamak agar masalah dapat diselesaikan, sehingga dengan cara ini masalah sejak awal sudah dapat dicarikan jalan keluarnya (tidak perlu berujung dengan perceraian). Jika masalah tidak dapat selesai ditingkat kaum (diistilahkan dengan ranji keturunan), masalah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ditingkat Jorong, dan dari jorong baru dibawa ke Nagari. Praktek ini kini sayangnya tidak lagi berjalan, bahkan ada kecenderungan untuk membawa masalah langsung ke Pengadilan Agama mengingat kebijakan yang ada, bahkan tanpa perlu menanyakan BP4 Nagari. Informan menduga hal ini ikut berkontribusi pada banyaknya pertikaian suami-istri yang berujung menjadi perceraian (cerai talak maupun cerai gugat), dengan kata lain menjadi salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya perceraian. Terkait dengan keterlibatan ninik-mamak dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat Minang meyakini bahwa para ninik mamak (diistilahkan sebagai bundo kandung) fungsinya diibaratkan sebagai pemegang anak kunci rumah tangga, yaitu mereka yang memegang (perlu mengetahui, pen) segala seluk-beluk persoalan rumah-tangga yang terjadi pada para kemenakannya. Karena pertalian hubungan ini muncullah perasaan ado raso badunsanak, rasa batatanggo, rasa berkorong kampuang, yang memberi efek orang tidak mudah mengajukan perceraian. “Saya akan bercerai dengan anaknya, padahal istri saya kemenakan bapak saya.” Rasa inilah yang diperhatikan di Minangkabau, yaitu bahwa kalau bercerai hancurlah persaudaraan, mengingat segala macam ada sangkut-pautnya. 4.4. Uraian Kasus 1 Hasil wawancara dengan H. Aresno Dt. Andomo, S. Ag pada 18 April 2015, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan Pariangan (Nagari Tuo Minangkabau), Tanah Datar. Selain itu narasumber sudah bertugas di KUA selama 19 tahun dan pernah menjadi KUA teladan. 19 Dalam studi ini didalami tiga kasus cerai gugat, yaitu kasus EL-OS, IK-IB, dan Fat-Fik, yang masing-masing berkontribusi memberi gambaran spesifik mengenai fenomena yang dieksplore. 4.4.1. Kasus EL-OS: Dominasi Keluarga Suami atas Suami. Masa Perkenalan hingga Pernikahan. EL merupakan perempuan terdidik yang menamatkan program diploma tiga (D3) pada tahun 2005 dan setelah bekerja melanjutkan pendidikannya (tahun 2010) hingga tamat S1. Lahir dan besar di Padang, adat Minang di dalam keluarga EL tidak lagi dipraktekkan mengingat keluarga ibunya lama merantau ke Medan. Meski sudah tidak melaksanakan adat Minang, mamak (paman EL yang tinggal di Pondok Gede) masih melaksanakan peran penting. Saat EL hendak memutuskan apakah akan menikah dengan OS atau tidak, peran mamak EL sangat dominan. Mamak EL satusatunya anggota keluarga yang bertemu langsung dengan OS, yang dimungkinkan karena Mamak EL tinggal di Pondok Gede sementara OS di Bekasi, Mamak EL lah yang ditemui OS dan keluarga (Ibu OS dan kakak OS) untuk meminta agar EL bersedia menjadi istri OS. Tentang perkenalan EL dengan suami (OS), terjadi melalui perantaraan teman kampus EL yang meminta EL mencermati profil OS pada akun FB milik OS mengingat EL dan OS tinggal berjauhan. EL di Padang, sementara OS di Tambun, Bekasi. Setelah OS menghubungi EL lewat telpon sebagai tanda ketertarikannya, perkenalan dilanjutkan dengan menggunakan fasilitas chatting baik melalui FB maupun HP (video call). Karena keduanya merasa mantap, EL meminta OS berkunjung ke rumah mamak EL (kakak ibu EL) yang tinggal di Jakarta untuk berkenalan. OS datang ke rumah Mamak EL ditemani ibu dan kakak kandungnya (OS anak kedua dari dua bersaudara) serta suami kakaknya (kakak ipar OS). Setelah mamak EL memberi respon positif terhadap OS dan kelaurga, EL mantap meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan. Menjelang hari raya pada Juni 2012 EL dan OS pun menikah. Sebagaimana tradisi Minang, prores diawali dengan silaturahim keluarga laki-laki ke rumah perempuan, sebagai pertanda persetujuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan dilanjutkan dengan kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki untuk meminang (manjapuik). Tentang waktu pelaksanaan pernikahan, EL sebenarnya menginginkan agar pernikahan dilaksanakan di akhir tahun, yaitu dibarengkan dengan kakak pertama EL yang juga akan menikah. Alasan lain karena kuliah EL belum selesai. Akan tetapi karena OS dan keluarga (terutama kakak OS) tidak berkenan, EL dan keluarga mengalah. Bibit-bibit konflik berupa adanya intervensi kakak (keluarga OS) yang berlebihan sebenarnya mulai tampak, akan tetapi EL dan keluarga tidak menyadari. Tentang hal ini paman EL mengatakan,“Kalau saya liat, keluarganya sih bagus-bagus saja. Hubungan mereka bersaudara kelihatan akrab, baik sekali. Cuma kalau menurut saya penyebab masalah EL itu karena sangat baiknya hubungan mereka. Terlalu dekat. Karena ibunya hanya punya dua anak. Inilah yang menurut saya penyebabnya.” Pada awal pernikahan, EL dan OS sudah langsung berhadapan dengan ujian berat. OS diberhentikan dari tempat bekerja beberapa hari saja setelah pernikahan. Karena suami tidak lagi bekerja, tiga bulan setelah pernikahan, EL yang tetap tinggal bersama ibunya untuk menuntaskan studi dan sekaligus mengurus pemberhentian dirinya dari tempat bekerja, harus membiayai sendiri kebutuhan dirinya. Bahkan ketika EL datang ke Jakarta menyusul suaminya untuk sementara waktu (hanya tiga minggu mengingat skripsi EL meski sudah selesai masih belum diujikan), EL terpaksa menggunakan uang simpanan pribadi (uang pesangon) untuk kebutuhan sehari-hari (termasuk membeli tiket JakartaPadang PP dan keperluannya selama di Jakarta, sebagian dari keperluan OS, bahkan keperluan keluarga OS mengingat EL tinggal satu atap dengan mereka (kakak OS serta ibu OS). Akibatnya uang pesangon EL habis untuk membayar aneka kebutuhan tersebut. 20 Keributan mulai terbuka saat EL untuk sementara waktu tinggal bersama OS di rumah kakak OS; dan semakin menjadi-jadi saat EL kembali datang ke Jakarta beberapa bulan kemudian, segera setelah urusan kuliahnya benar-benar rampung dan ia sudah berhenti dari bekerja. Sumber utama konflik adalah keinginan EL untuk tinggal terpisah dari keluarga OS (tidak tinggal di rumah kakak OS), yang sebenarnya merupakan kesepakatan EL dan OS sebelum menikah. Selain itu EL merasa tidak nyaman mengingat EL dan OS bukan tinggal di rumah orang tua OS, akan tetapi di rumah kakak OS yang sudah berkeluarga dan mempunyai tiga anak. Hal lain karena OS sudah memiliki rumah sendiri meskipun kecil, serta karena EL dan OS sudah mencari kontrakan (dan membayar uang muka) sehingga EL tidak melihat ada alasan mengapa mereka harus bertahan tinggal di rumah kakak OS. Keributan demi keributan terjadi. Bukan hanya dengan kakak OS, belakangan juga melibatkan ibu OS. Masalah pun berkembang dari ketidak-setujuan EL dan OS keluar dari rumah hingga perilaku sehari-hari EL yang selalu dinilai buruk. Menurut penuturan EL, kakak dan ibu OS memperlakukannya dengan tidak baik. Berbagai urusan rumah-tangga di serahkan pengerjaannya kepada EL sementara EL sedang hamil. OS yang awalnya membela EL belakangan tampak mendua bahkan akhirnya kerap membela kakak dan ibunya. Apapun yang dilakukan EL dinilai salah. Konflik memuncak ketika EL dan OS akhirnya pindah ke rumah OS. Tapi hanya berlangsung tiga minggu, setelah itu EL diminta OS pulang ke Padang dengan alasan agar dapat melahirkan di Padang padahal sebelumnya OS meminta orangtua EL datang ke Jakarta untuk menemani EL melahirkan. Ketika EL sudah di Padang (sebelum melahirkan), ibu OS sempat datang ke Solok (ke rumah kerabatnya) bahkan tinggal cukup lama (hingga lebaran). Akan tetapi Ibu OS tidak mau mendatangi EL, bahkan meminta EL yang mendatangi Ibu OS di Solok. Mengikuti nasihat OS agar EL mendatangi ibunya, meski berat mengingat kehamilan EL sudah memasuki usia delapan bulan akhir, EL pergi ke Solok ditemani ayahnya. Sesampai di Solok EL tidak berhasil bertemu ibu OS karena ibu OS pergi entah kemana. Belakangan EL tahu bahwa ibu OS sengaja bersembunyi karena tidak ingin bertemu. Ketika lebaran, EL dan keluarga datang mengunjungi keluarga OS di Solok dan ibu OS yang masih tinggal disana. Akan tetapi EL hanya menerima kemarahan, karena dinilai tidak tahu adat. EL hanya membawa kue-kue dan tidak membawa makanan lengkap sebagaimana kebiasaan di keluarga OS. Saat lebaran, OS juga datang ke Padang. Meski sempat bermalam di rumah orang tua EL, akan tetapi OS lebih banyak tinggal di Solok. Saat hari raya itu pula EL mendapat informasi dari kerabat OS di Solok bahwa orang-tua dan kakak OS serta OS sudah tidak menyukai EL dan akan menceraikan EL setelah EL melahirkan. Ketika EL melahirkan, OS yang sudah kembali ke Jakarta datang ke Padang. Akan tetapi karena bangun kesiangan, ia ketinggalan pesawat dan terpaksa dipinjami uang untuk membeli tiket oleh orang tua EL agar dapat berangkat ke Padang karena mengeluh tidak mempunyai uang. OS yang hanya semalam tinggal di Padang kembali ke Jakarta karena harus bekerja, adapun kakak dan ibu OS tidak pernah mau melihat anak EL hingga kini. EL sudah mengikuti arahan OS untuk mengirim SMS kepada Ibu dan kakak OS untuk memberitahu bahwa ia sudah melahirkan. SMS EL tidak pernah dibalas. Satu-satunya SMS yang dikirim ibu OS berisi luapan kemarahan dan sumpah-serapah, diantaranya menyebut anak EL sebagai anak setan. Setelah OS mentalak EL tak lama setelah EL melahirkan, EL menceritakan berbagai peristiwa yang dialaminya. Sehari setelah mentalak EL (melalui telfon) OS sempat mengirim SMS kepada EL mengajak rujuk dengan persyaratan EL dan keluarga harus datang ke Jakarta karena Ibu dan kakaknya tidak mau datang menemui EL dan 21 keluarga di Padang. EL dan keluarga menilai hal tersebut sebagai penghinaan. Mereka mendiamkan saja dan menunggu apakah OS akan mendatangi anak dan istrinya. Setelah itu praktis tidak ada kontak antara EL dengan OS, hingga EL melakukan gugatan cerai. Selama itu pula OS tidak pernah mengirim uang. elakangan tersiar kabar bahwa OS sudah menikah dan sudah pula memiliki anak. Proses Gugatan Cerai. Proses gugatan cerai tidak berlangsung lama. Setelah EL menceritakan perihal masalah rumah-tangganya tak lama setelah OS menyatakan talak kepadanya melalui telpon, kedua orang tua dan mamak EL yang tinggal di Jakarta dapat menerima keinginan EL untuk menggungat cerai. Hal itu karena setelah OS menyatakan talak tidak lagi ada kabar berita dari OS dan mereka melihat EL memerlukan kejelasan status untuk masa depannya. Gugatan cerai dilakukan pada Mei 2014, sementara SK keluar pada Agustus 2014. Menurut penuturan pihak PA, keputusan dapat lebih cepat karena pihak laki-laki (OS) yang tinggal di Jakarta tidak pernah datang dalam persidangan meski surat undangan sudah dilayangkan dan dinyatakan sampai atau diterima oleh pihak yang bersangkutan. Selama proses gugatan cerai EL didampingi oleh ayahnya, sesekali ditemani sepupunya yang juga bertindak sebagai saksi dalam proses cerai gugat tersebut. Paska Gugatan Cerai. Sejak kembali ke rumah orang tua untuk melahirkan hingga akhirnya suami mentalak lewat telepon dan EL mengajukan cerai gugat, EL tinggal di rumah orang tuanya bersama kakak perempuannya yang sudah menikah dan juga adikadiknya. Peran pengasuhan karena hal itu ditangani bersama oleh orang tua dan kakak serta ipar dan adik-adik, yang menyayangi anak EL sebagaimana layaknya menyayangi anak dan kemenakan. Karena hal itu EL tidak terlalu menghadapi masalah terkait pengasuhan, mengingat adanya peran dari keluarga besar. Problem yang agak berat dirasa EL terkait masalah ekonomi karena ia tidak bekerja dan tidak mempunyai tabungan saat ditelantarkan suaminya. Akan tetapi karena EL menilai kejelasan status pernikahan lebih penting dan ia yakin akan memperoleh pekerjaan mengingat ia sebelumnya sudah punya pengalaman kerja serta adanya dukungan penuh dari orang tua, kakak, adik serta kerabat termasuk mamaknya yang tinggal di Pondok Gede; EL mantap dengan keputusannya menggugat cerai. Tak lama setelah gugatan cerai dilakukan EL yang sudah mengirimkan sejumlah lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan akhirnya mendapat panggilan kerja. Ketika studi dilakukan, EL sedang melewati masa jobtraining dan optimis dapat terus bekerja di perusahaan tempatnya bekerja. Keberadaan keluarga besar dalam pengasuhan anak juga membantu EL berkonsentrasi penuh pada pekerjaan, karena ia dapat meninggalkan anak di rumah dengan tenang saat ia bekerja mengingat anak didampingi oleh orang-orang yang menyayanginya (nenek dan tantenya). Lingkungan sekitar begitu pula kerabat tidak seluruhnya tahu bahwa EL sudah bercerai bahkan ia yang melakukan gugatan cerai. “Biarlah mereka tahu sendiri. Saya tidak ingin ramai-ramai (membicarakannya, pen). Tidak ada gunanya…” Namun mereka yang tahu umumnya memahami posisi EL dan berempati padanya. Karenanya EL tidak mendapat perlakuan negatif dari sekitar atas tindakan cerai gugat yang dilakukannya. Menurut EL kalaupun orang-orang yang kini belum tahu bahwa dirinya sudah bercerai nantinya tahu, EL yakin mereka akan memahami jika diberi penjelasan.“Sekarang masyarakat sudah pintar. Kalau diberitahu akan paham.” EL kini hanya ingin membesarkan anaknya dan menekuni pekerjaannya dengan baik dan belum berfikir apakah akan menikah lagi atau tidak. Ia yakin akan dapat melewati masa sulit yang kini dialami dengan baik, diantaranya karena dukungan penuh keluarga besar. “Belum ada terpikir (untuk menikah lagi, pen). Mau konsentrasi membesarkan anak dan bekerja. Tapi saya optimis saya bisa. Saya bersyukur papa dan mama serta kakak dan adik serta uwo di Jakarta dan famili lain sangat mendukung… Saya merasa lebih baik. Sekarang semua jadi jelas…” 22 4.4.2. Kasus IK dan IB: Campur Tangan Keluarga Perempuan atas Perempuan. Masa Perkenalan hingga Pernikahan. IK (31 tahun) berpindidikan S1, usia dua tahun lebih tua dari IB, berasal dari keluarga berada. Ayahnya bekerja di Pemprov Sumatera Barat dan pernah menjabat sebagai kapala dinas. Ibunya pun orang yang berpendidikan, yaitu guru di sebuah SLTA, yang sengaja pensiun dini agar dapat mengurus anak dan cucunya. Secara ekonomi IK tergolong cukup mampu. Sejak sebelum menikah sudah bekerja, yaitu sebagai tenaga MLM pada sebuah produk herbal yang cukup ternama di Kota Padang. Adapun IB, tingal dan lahir di Padang Panjang meski berasal dari Pariaman. Orang tua lama merantau ke Bukit Tinggi, sehingga kerap merasa lebih sebagai orang Bukit Tinggi ketimbang orang Pariaman. Sebagaimana halnya IK, IB berasal dari keluarga terpandang dan cukup mampu. Bapaknya mantan rektor di salah satu universitas negeri di Sumatera Barat, sementara ibunya kini dekan di salah satu perguruan tinggi negeri. Lahir sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, IB yang menyukai seni sangat halus perasaannya. Ia mengenal IK sebagai teman satu kampus dan telah menjalin hubungan beberapa tahun selama mereka kuliah hingga akhirnya menikah. Menikah dengan perayaan cukup mewah mengingat kedua orang tua pasangan suami istrri ini merupakan pejabat terpandang, IK dan IB yang setelah menikah tinggal di rumah ibunya semula merupakan pasangan yang cukup berbahagia. Masalah mulai muncul karena IK tidak puas dengan keuangan IB yang dinilainya tidak memadai. IB yang seniman menurut IK tidak bekerja maksimal, sehingga IB hanya bisa membawa pulang uang sedikit. IK menilai IB malas dan tidak bertanggung-jawab, namun dalam perspektif IB dan keluarga persoalan tidak seperti itu. Tentang tidak bekerja maksimal, IB yang bekerja dibidang seni memang memiliki dinamika pekerjaan berbeda dengan pegawai kebanyakan. Ia tidak beroleh uang setiap bulan secara rutin, akan tetapi tergantung pada pertunjukkan yang diselenggarakan. Semenetara itu IB menilai IK tidak dapat memahami keinginannya untuk berusaha, karena terlalu memilih-milih jenis pekerjaan. Ketika IB hendak membuka toko misalnya, IK keberatan karena menilai tidak layak dengan kondisi ekonomi dirinya dan keluarga. Perbedaan pandang juga terjadi mengenai apa yang menjadi penyebab retaknya rumah-tangga IK dan IB. Jika menurut IK karena IB malas dan kurang berusaha, keluarga IB menilai persoalan karena IK kurang menghargai IB. IK dan IB yang tinggal di rumah orang-tua IK paska menikah menurut keluarga IB kerap memperlakukan IB dengan tidak baik. IB yang merupakan anak dari keluarga terpandang karenanya merasa terhina. Sebagai contoh ketika kakak iparnya pulang bekerja, IB diberi tugas membuka dan menutup pintu garasi. IB melalui lisan orang-tuanya menilai IB kurang mendapat pelayanan yang baik. Ia diperlakukan sebagai orang yang tinggal menumpang dan bukan sebagai suami (tidak ada keleluasaan mengambil lauk-pauk dan makan seolah dicatu). IK juga kerap bicara dengan suara keras sementara IB yang sangat halus dan perasa tidak pernah diperlakukan seperti itu di rumah orang tuanya. “Anak saya tidak dihargai dirumah isterinya. Kita harus menyadari bahwa perempuan memang di bawah laki-laki kalau di Minang ini… akan tetapi karena sekarang perempuan sudah merasa tinggi, laki-laki jadi kurang dihargai...” Konflik antara IB dan IK relatifbersifat tidak terbuka. IB yang pendiam lebih banyak memendam rasa. Ketika kesabarannya hilang, ia menghindar dengan memilih pulang ke rumah orang-tuanya. Puncaknya ketika ia meninggalkan rumah isteri dan pergi ke luar Padang. Saat itu IB sudah tidak lagi ingin meneruskan perkawinan karena merasa sudah tidak lagi ada kecocokan. IB pergi dari rumah pada saat IK sedang hamil enam bulan dan tidak lagi pernah ada kontak dengan IK hingga IK mengajukan gugatan cerai. IB bukan tidak ingin memberi nafkah setelah ia pergi dari rumah, namun menurut keluarga IB, IK 23 selalu menampik pemberian IB karena merasa sudah cukup secara materi. IB menyimpan uang yang sedianya diberikan kepada IK untuk biaya pengasuhan anaknya, dengan rencana akan diberikannya kelak jika waktunya lebih kondusif. Gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan pada Februari 2015 dan sudah mendapat SK putusan pada bulan Maret (kurang dari satu bulan). Sebagaimana diungkap ibu IB, putusan terlalu cepat bahkan mereka tidak tahu bahwa putusan sidang sudah dikeluarkan karena hanya sekali menerima panggilan sidang. Mereka masih menunggu-nunggu pemanggilan berikutnya, bahkan ibu IB menunggu kesempatan untuk dapat bersaksi, sementara putusan ternyata sudah keluar. Saat sidang pertama IB memang tidak datang karena khawatir kemarahannya terbuka di forum selain karena bekerja dan tinggal di luar kota. Namun ia tidak menduga bahwa itu menjadi panggilan sidang satu-satunya dalam proses cerai gugat tersebut dan keputusan segera keluar. Selama proses cerai gugat, IK ditemani ibu dan kakak laki-lakinya yang mendukung penuh keputusan IK dan yang sekaligus menjadi saksi selama proses persidangan. Paska Cerai Gugat. IK yang tinggal bersama ibu dan kakaknya yang juga sudah menikah dan mempunyai anak, sebagaimana halnya EL, banyak terbantu dengan keberadaan keluarga luas (ibu dan kakaknya) terutama dalam peran pengasuhan. Untuk ekonomi IK juga banyak terbantu, selain ia juga mempunyai penghasilan tetap meski tidak banyak. Respon masyarakat sekitar tempat IK tinggal tidak terlalu terlihat mengingat IK tinggal di perumahan elit yang cenderung agak individualis. Selain itu keberadaan orangtua IK yang merupakan tokoh menyebabkan IK tidak terlihat memiliki beban dengan keputusan cerai gugat yang dilakukan. Saat ditanya mengenai perasaan dirinya, IK menjawab bahwa ia kini merasa lega karena sudah resmi dapat berpisah dari IB. IK sama sekali tidak mengajukan tuntutan pembiayaan (nafkah) kepada IB paska bercerai, yang menurut penuturan IK dilakukan agar proses dapat berlangsung cepat sebagaimana diutarakan petugas PA. Karena hal itu dalam putusan cerai IB sama sekali tidak diwajibkan memberi nafkah kepada IK, meski IK ditetapkan mendapatkan hak pengasuhan. 4.4.3. Kasus FAT dan FIK: Isteri dengan Pendidikan Rendah dan Usia Relatif Muda Proses Perkenalan hingga Pernikahan. Berbeda dengan EL dan IK yang berpendidikan tinggi (sarjana), Fat hanya taman SLTA, itu pun setelah ia bersekolah di enam sekolah, karena setiap tidak naik kelas pindah sekolah. Menikah pada usia 19 tahun, Fat secara emosional tidak stabil (meledak-ledak). Saat diwawancarai Fat nampak masih sangat geram terhadap mantan suaminya. Ketika nama FIK disebut, kemarahan Fat langsung terlihat. Fat merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Keluarga Fat dapat dikatakan secara ekonomi kurang. Kakaknya sempat bekerja sebagai buruh di Jakarta, akan tetapi kini menanggur dan tinggal bersama orang tuanya di Lubuk Minturun, yang letaknya agak di pinggir Kota. Sedangkan orang tua Fat hanya buruh tani (ladang) dengan penghasilan terbatas. Fat kini bekerja pada home industri didepan rumah, yaitu membantu pengerjaan pengemasan penganan yang diproduksi home industri tersebut. FIK berasal dari keluarga dengan status sosial rendah. Berasal dari keluarga besar dengan jumlah saudara hingga dua belas orang, bapak dan ibu Fik yang bekerja sebagai buruh tani (ladang) tidak mengecap pendidikan cukup. Bapak Fik yang sudah cukup berusia bahkan tidak dapat mengingat nama anak-anaknya (apalagi urutan kelahiran anakanaknya), bicara dengan tutur kata yang agak kasar dan dengan suara keras, yang sekaligs menunjukkan kemampuan intelektual dan status sosial ekonomi keluarga tersebut. FIK menikah pada usia 24 tahun (saat bercerai usia 27 tahun) dan sudah mempunyai pekerjaan cukup baik disebuah pabrik besar di Kota Padang pada saat menikah 24 dan masih bekerja disana hingga kini. Perkenalan Fat dan Fik difasilitasi oleh kerabat Fik, yang kebetulan kenal baik dengan Fat. Perkenalan berlangsung setahun lebih, hingga kemudian keduanya memutuskan meneruskan ke jenjang pernikahan. Mereka menikah pada Februari 2011, dikaruniai satu anak yang lahir pada Juli 2012. Setelah menikah, Fat dan Fik sebagaimana tradisi Minang, tinggal di rumah perempuan (Fat). Pernikahan mereka awalnya penuh kebahagiaan. Akan tetapi karena Fat suka membentak-bentak, berteriak, meraung-raung bahkan pernah berguling-guling dipelataran saat marah; keributan demi keributan tak terhindarkan. Persoalan kecil menjadi besar karena mendapat respon berlebihan dari Fat. Selain suka mengamuk, Fik mengeluhkan Fat yang kerap datang ke kantor Fik dan mengamuk disana dan membuat Fik malu. Adapun Fik menurut Fat berubah kasar setelah menikah karena terlibat perjudian. Konflik memuncak ketika Fik meninggalkan rumah Fat dan membawa semua barangbarangnya, sebagai pertanda bahwa ia sudah tidak ingin meneruskan pernikahannya dengan Fat. Fat yang tidak terima mendatangi Fik dan mengamuk di rumah Fik, meminta Fik kembali ke rumah. Fik tidak menggubris. Kondisi bertambah parah karena bapak Fat juga bereaksi keras, melabrak Fik sambil membawa parang. Fik tidak juga kembali hingga Fat melahirkan, bahkan hingga anaknya sudah bisa berjalan. Sesekali Fik ada memberi nafkah kepada Fat dan hal itu memicu kemarahan Fat dan mendorong Fat melabrak Fik ke kantor. Proses Cerai Gugat. Karena Fik tidak kunjung kembali dan tidak memberi nafkah, Fat atas masukan keluarga dan teman menggugat cerai Fik. Gugatan cerai diajukan Fat pada bulan Mei 2013 dan keluar putusan pada Juni 2003. Sebagaimana halnya IK, putusan gugatan cerai Fat sangat cepat, yaitu hanya sebulan setelah diajukan. Meski di dalam SK cerai disebutkan bahwa Fik dihukum untuk membayar nafkah setiap bulannya (sebesar lima ratus rupiah), nafkah tersebut tidak pernah diberikan kepada Fat paska putusan cerai gugat keluar hingga kini. Keluarga Fik memang pernah memberi uang saat anak Fat dan Fik berulang tahun, akan tetapi bersifat temporal. Fat dan keluarga pun tidak terlalu paham haknya, karena mereka tidak mengerti bahwa Fik diwajibkan memberi nafkah (di dalam SK disebutkan menghukum) untuk perawatan anak Fik dan Fat. Paska Cerai Gugat. Paska cerai gugat Fat masih terlihat terguncang dan belum dapat menerima. Kemarahan masih jelas terlihat pada wajah Fat yang bereaksi negatif ketika nama Fik disebut atau ketika kasusnya ditanyakan kembali. Untuk pengasuhan Fat mengandalkan dukungan keluarga, namun karena keluarga bukanlah orang yang mengerti pendidikan anak, pengasuhan dilakukan seadanya tanpa pengetahuan yang memadai (oleh ibunya yang sudah agak sepuh atau kakaknya yang belum menikah dan kini menganggur). Fat terbantu dengan dukungan tugas pengasuhan dari keluarga besar, terlbeih lagi karena Fat yang belum dapat berdamai dengan masalah yang dihadapinya cenderung tidak fokus pada pengasuhan anaknya. Ia disibukkan dengan urusan dendamnya kepada mantan suaminya.Lingkungan sekitar tempat tinggal Fat yang masih bernuansakan pedesaan cenderung menilai perceraian sebagai aib. Karena itu respon negatif lingkungan masih kerap diterima Fat selain karena karakter Fat yang temperamental. Meski demikian Fat diuntungkan karena kini sudah mempunyai pekerjaan, sehingga perlahan-lahan dapat mengalihkan kemarahannya pada hal lain yang lebih produktif (bekerja). 4.5. Analisis Kasus 4.5.1.Faktor Penyebab Istri Menggugat Cerai Suami. Merujuk pada tiga kasus sebagaimana telah diuraikan, faktor penyebab istri menggugat cerai yang utama karena adanya penelantaran oleh pihak suami (suami pergi meninggalkan istri tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah). Perginya suami dari rumah (untuk kasus EL istri diminta kembali ke rumah keluarganya namun tidak kunjung dijemput pulang) bukan karena ketidak-mampuan ekonomi, akan tetapi sebagai isyarat bahwa pihak 25 suami sudah tidak lagi ingin meneruskan pernikahan, baik karena ketidak-cocokan terhadap pribadi istri (Kasus Fat dan Fik serta IB dan IK) maupun sebagai akibat ikut campurnya orang tua dan keluarga dalam pernikahan (kasus EL-OS). Temuan ini berbeda dengan kebanyakan tstudi perceraian yang menempatkan faktor ekonomi selalu sebagai penyebab dominan, yang sekaligus menunjukkan bekerjanya faktor-faktor non-materi pada kasus-kasus tertentu. Mengenai mengapa pihak istri menggugat cerai, hal itu bukan karena peningkatan kemampuan ekonomi perempuan (independensi perempuan) dan juga bukan karena kesadaran gender yang makin baik. Pada tiga kasus yang di dalami, bekerjanya perempuan bukan menjadi penyebab perceraian, akan tetapi perempuan bekerja justru untuk mempertahankan diri paska perceraian. Alasan cerai gugat lebih sebagai upaya perempuan memperjelas status atau keberadaannya dalam pernikahan, mengingat dengan kondisi status yang tidak jelas, perempuan berada pada kondisi yang lebih buruk dibandingkan jika ia melakukan cerai gugat (rational choice theory). Adanya dukungan dari keluarga besar dan penilaian masyarakat yang makin objektif teradap kasus perceraian, menyebabkan kalkulasi atas tindakan cerai gugat dinilai lebih menguntungkan, dibandingkan dengan kondisi tidak memiliki status yang jelas dalam pernikahan. Mengenai adanya dukungan dari keluarga besar, hal itu sekaligus menunjukkan masih eksisnya keluarga besar di Padang, meski terbatas pada ibu, bapak, serta kakak dan adik, sementara peran ninik-mamak kalau pun ada tidak terlalu menonjol. Dukungan diberikan keluarga besar dengan tujuan untuk mengeluarkan perempuan dari penderitaan akibat pengabaian, yang secara konkrit disaksikan langsung oleh keluarga besar. Yang menjadi pertanyaan, mengapa suami tidak menceraikan istri jika memang sudah tidak lagi menginginkan dan membiarkan istri yang melakukan tindakan untuk bercerai? Alasan keengganan pihak suami untuk mengeluarkan uang guna mengurus perceraian serta tidak ingin repot, dapat diduga menjadi penyebab terjadinya pembiaran meski pihak suami sudah tidak lagi ingin meneruskan perkawinan. Pada sisi lain, hal ini menunjukkan semakin tidak bekerjanya kontrol sosial masyarakat, sehingga tindakan pengabaian (tidak melaksanakan peran, tidak memenuhi kewajiban) terhadap istri dan anak, dapat berlangsung lama tanpa ada respon apapun dari sekitar. Dalam konteks masyarakat Minang, hal ini sekaligus menunjukkan sudah tidak bekerjanya (tidak hidupnya) pranata sosial masyarakat setempat yang bersumber dari adat istiadat dalam mencegah tindakan penyimpangan. Kontrol atas masyarakat melalui peran ninik-mamak sebelumnya dalam kurun waktu cukup lama efektif mencegah berbagai tindakan penyimpangan yang ada (hamil diluar nikah, berhubungan dengan bukan muhrim, perjudian, dan lain-lain), yang pada akhirnya sekaligus menjaga keutuhan keluarga dan kesucian lembaga pernikahan. Akan tetapi seiring dengan makin menurunnya peran ninikmamak (terutama peran ekonomi) baik karena tantangan internal pada diri ninik-mamak yang harus berkonsentrasi memenuhi kebutuhan (termasuk kebutuhan ekonomi) diri dan keluarga sehingga peran membimbing (dan menafkahi) anak kemenakan menjadi terabaikan, ninik-mamak juga kehilangan saham untuk dapat melaksanakan peran yang lebih besar (pengawasan, penasihatan). Karenanya dalam banyak kasus ninik-mamak hanya menjadi stempel atas kebijakan yang diambil, dengan penguatan peran pada ayah bahkan pada individu itu sendiri (makin individualis). Meski upaya-upaya ke arah penguatan kembali bundo kanduang (ninik-mamak) terus dilakukan, diantaranya dengan memunculkan kembali lembaga adat melalui pembentukan institusi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Minang (LKAM), akan tetapi kuatnya muatan politis pada kehadiran institusi ini (terutama LKAM), menyebabkan efektifitasnya tidak terlalu dapat diandalkan. Untuk KAN, meski dibeberapa Nagari mulai berperan, peran yang dilaksanakan baru sebatas pada pengurusan 26 tanah adat atau tanah pusaka dan belum masuk ke ranah pernikahan. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat KAN baru dikembangkan ditingkat Nagari (Kecamatan), sementara ditingkat jorong bahkan desa serta kaum, yang sangat mungkin berperan mengurus masalah pernikahan (penanaman nilai-nilai tentang berkeluarga dan konsultasi pernikahan), belum lagi terlihat. Ditingkat Nagari KAN juga mulai difungsikan sebagai BP4 (disebut dengan BP4 Nagari), namun belum efektif untuk semua kecamatan. Persoalan lain, mengapa pihak suami meninggalkan istri? Untuk kasus EL, faktor campur tangan keluarga suami (ibu dan kakak perempuan), terutama dalam urusan kebebasan pasangan suami istri tersebut untuk tinggal terpisah dari keluarga suami, menjadi faktor utama. Hubungan antar anggota keluarga yang terlalu kuat (antara ibu dan anak laki-lakinya serta antara kakak perempuan dengan adik laki-lakinya) menjadikan pihak ibu dari suami EL serta kakak kandung OS tidak dapat (kurang dapat berempati akan kebutuhan keluarga baru tersebut terutama kebutuhan pihak istri adiknya atau kebutuhan menantunya). Hal tersebut menjadi semakin buruk ketika suami-istri tinggal terpisah (istri kembali ke rumah orang tua) dan juga diperparah dengan ketidak-sabaran pihak suami untuk menunggu konflik mereda serta sikap pro-aktif pihak suami untuk menyelesaikan masalah. Kondisi menjadi makin sulit ketika dalam kondisi penuh konflik pihak suami justru memutuskan untuk menikah lagi. Pada tahap ini (pengabaian pihak suami terhadap istri dan anak yang dikandung serta keputusan suami menikah lagi sementara masalah belum selesai), memantapkan pihak istri untuk mengajukan gugatan cerai. Hal tersebut relatif mirip dengan kasus IK meski dengan bentuk agak berbeda. Jika konflik dalam rumah tangga EL dipicu oleh dominasi keluarga suami atas diri suami, pada kasus IK dominasi keluarga istri yang memunculkan sikap kurang penghargaan isteri terhadap suami yang tinggal di rumahnya yang menjadi penyebab. Meski rumah IK yang berasal dari keluarga cukup mampu memungkinkan pasangan suami istri tersebut tinggal di rumah keluarga istri, namun jika pihak istri kurang dapat menunjukkan penghargaan terhadap suami mengingat laki-laki Padang umumnya perlu diperlakukan khusus karena kuatnya budaya patriarki. Terlebih lagi karena suami IK datang dari keluarga terpandang dengan status sosial baik dan sekaligus pimpinan dari suatu kaum. Sikap yang tidak baik (kurang menghargai) bukan hanya akan melukai perasaan suami, akan tetapi sekaligus menimbulkan penolakan dari keluarga besar suami karena dinilai merendahkan keluarga besar. Karenanya kemampuan perempuan untuk melakukan penyesuaian perangainya terhadap kebiasaan yang hidup dimasyarakat, menjadi kebutuhan mutlak guna menjaga keutuhan rumah-tangganya. Perbedaan karakter antara suami dan istri pada kasus IK dan IB juga perlu dicermati, karena meskipun keduanya datang dari keluarga terpandang dan dengan status pendidikan yang sama tingginya, akan tetapi penyesuaian masing-masing pihak terhadap karakter personal pasangan, persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian. Hal ini sekaligus memunculkan pertanyaan, mengingat pada ketiga pernikahan yang kasusnya didalami, meski pernikahan diawali dengan perkenalan (berpacaran) bahkan pada kasus IK-IB berpacaran setahun lebih, ternyata tidak membantu masing-masing pihak untuk saling mengenal karakter pasangannya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa proses berpacaran yang kerap ditengarai sebagai tahapan saling mengenal, tidak selalu terjadi karena masing-masing pihak masih harus beradaptasi dengan agak sulit setelah menikah. Merujuk Levinger, hal-hal tersebut dapat menjadi faktor terjadinya pembusukan atau pengrusakan dalam kehidupan pernikahan, yaitu ketika secara kalkulatif atas reward (kesenangan) yang diperoleh dari pernikahan dinilai tidak sebanding dengan kesulitan (aneka konflik) yang ditimbulkan. Yang tidak kalah penting, temuan penelitian juga menunjukkan, pasangan suami-istri kini tidak lagi melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sacral sehingga harus dipertahankan dengan upaya maksimal (diperjuangkan eksistensinya dengan sepenuh daya). Hal tersebut setidaknya terindikasi dari menurunnya daya tahan 27 keluarga dalam menghadapi masalah, yang kerap dengan mudah menjadikan perceraian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Peningkatan angka perceraian diduga diantaranya terjadi karena hal ini, yaitu karena semakin rendahnya ketahanan keluarga, terutama pada keluarga dengan usia pernikahan lima tahun atau kurang. Hal ini juga membenarkan proposisi bahwa semakin lama pasangan menikah, semakin kecil kemungkinan terjadi perceraian. (http://freesociologybooks.com/sociology_Of_The_Family/12_Divorce_and_Separation. php). Proses perceraian yang makin mudah (dan murah), juga dapat diduga menjadi faktor mengapa sebagian orang menjadikan perceraian sebagai pilihan solusi atas permasalahan yang dihadapi, tanpa mempertimbangkan ekses negatif yang mungkin menyertai (terhadap anak misalnya). Rendahnya pemahaman yang benar tentang keluarga karena tidak berfungsinya sistem pembinaan masyarakat mengenai keluarga baik melalui keluarga, sekolah, maupun komunitas (masyarakat), menyebabkan pernikahan atau kehidupan berkeluarga termasuk perceraian kini dimaknai dalam arti berbeda (tidak lagi seagai institusi sakral yang perlu dipertahankan). 4.5.2. Dampak Cerai Gugat pada Institusi Keluarga. Pada kasus EL dan IK yang memiliki latar belakang pendidikan cukup baik (tamat S1) dan mempunyai kesanggupan untuk bekerja menafkahi diri sendiri dan anak meski dalam jumlah terbatas serta adanya dukungan keluarga pihak perempuan, dampak perceraian bagi EL dan IK meski pun meninggalkan kesedihan dan kemarahan akan tetapi tidak terlalu berdampak mengingat dampak ekonomi dapat diminimalisir. Terlebih lagi karena ketika mereka masih menikah pun suami dan keluarga tidak memberikan nafkah maksimal (istri masih terlibat dalam pembiayaan keuangan rumah-tangga). Pada kasus EL bahkan uang pesangon miliknya habis digunakan untuk keperluan rumah-tangga. Hal tersebut berbeda dengan kasus Fat yang berpendidikan SLTA dan tidak memiliki cukup ketrampilan serta kondisi keuangan yang terbatas. Selain itu lingkungan sosial FAT yang tinggal dipinggir kota (Lubuk Minturun), menyebabkan isu perceraian masih menjadi isu sensitif. Ketidak-sediaan FAT untuk diwawancarai (menjawab tapi hanya terbatas) dan ekspresi kemarahan FAT saat ditanyai, menjadi gambaran tentang hal tersebut. Begitu pula ekspresi kemarahan keluarga suami FAT atas kedatangan peneliti. Kurangnya pendidikan dan lingkungan sosial yang relatif agak tradisional, berpengaruh besar atas keberadaan keluarga pasangan tersebut. Masyarakat Minang umumnya, termasuk mereka yang tinggal di Kota Padang, masih kuat menganut extended family (keluarga luas) dalam hal ini keluarga pihak istri. Segera setelah menikah peran keluarga istri langsung dapat dirasakan, diantaranya dengan keharusan pasangan yang baru menikah tinggal di rumah keluarga istri (umumnya mereka baru meninggalkan rumah keluarga istri setelah mempunyai rumah sendiri). Tradisi ini tampak jelas pada disain Istana Baso Pagaruyung yang menempatkan anak-anak mereka yang sudah menikah masuk ke dalam rumah pusako (yang disebut pula sebagai Rumah Bundo Kanduang, masing-masing mendapat satu kamar). Meski beberapa tradisi Minang sudah mulai memudar, kembalinya anak perempuan ke rumah keluarga (orang tuanya) masih kuat dipraktekkan di masyarakat Minang di Sumatera Barat, termasuk di Padang. Karena itu pula peran pengasuhan anak umumnya tidak dilakukan sendirian, akan tetapi bersama-sama dengan keluarga istri (ibu, kakak atau adik, bahkan ipar). Pada pasangan yang belum mampu (belum memiliki rumah) tradisi ini sangat membantu, karena dapat mengurangi beban ekonomi keluarga muda tersebut (tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya mengontrak atau membeli rumah). Selain itu jika pasangan keluarga muda tersebut bekerja, keterlibatan keluarga istri dalam pengasuhan membantu mereka untuk 28 jangka pendek karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk upah pembantu. Begitu pula ketika terjadi perceraian, peran pengasuhan tidak terlalu berat dirasakan pihak istri (ketika mereka harus mengasuh anak setelah perceraian), karena orang tua dan kakak serta adikadik bahkan ipar ikut terlibat membantu. Apa yang terjadi pada IK, EL, dan FAT, ketiganya menunjukkan fenomena keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak. Pihak perempuan yang bercerai dapat mencari nafkah dengan lebih leluasa karena peran pengasuhan dilakukan oleh keluarga besar sementara ia bekerja. Bukan hanya dalam pengasuhan, kebutuhan ekonomi pihak perempuan yang bercerai juga ditanggung bersama oleh keluarga perempuan tersebut, meski kini sudah tidak lagi melibatkan ninik-mamak sebagaimana adat Minang. Back-up penuh keluarga dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi ini sedikit banyak memberikan kontribusi bagi perempuan yang rumah-tangganya bermasalah dalam mengambil keputusan untuk bercerai (menggugat cerai), meski pihak keluarga (pada ketiga kasus) tidak mendorong dilakukannya perceraian. Peran keluarga besar ini pun sangat membantu dalam mengurangi ekses negatif yang muncul pada keluarga, terutama pada peran pengasuhan dan ekonomi. 4.5.3. Respon Struktur Sosial atas Cerai Gugat. Respon struktur sosial terhadap cerai gugat relatif berubah ke arah yang makin objektif. Stigma negatif mengenai perceraian terutama untuk konteks kota, mulai berkurang. Masyarakat mulai melihat perceraian kasus per-kasus dalam memberi penilaian. Dari tiga kasus yang diteliti, dua kasus menunjukkan hal tersebut. Masyarakat kota yang makin kritis tidak lagi dengan serta merta memberi penilaian negatif terhadap tindakan perceraian, akan tetapi mencoba memahami lebih dalam sebelum memberikan penilaian. Hal tersebut berbeda pada masyarakat pinggiran dan tentu desa, yang masih cenderung merespon negatif kasus-kasus perceraian yang terjadi. Hal yang perlu dicermati terkait dengan peran PA sebagai institusi yang melakukan eksekusi atas permohonan perceraian. Tidak adanya kordinasi antara lembaga yang mengurus pernikahan (KUA), lembaga penasihatan pernikahan (BP4), dan lembaga yang mengeksekusi perceraian (PA); menyebabkan kehidupan berkeluarga dilihat sebagai sekuel yang terpisah: pernikahan satu hal, penyelesaian masalah satu hal, dan perceraian merupakan hal yang lain. Bukan hanya dilihat terpisah, akan tetapi terdapat perbedaan penanganan dan pendekatan. PA sebagai lembaga eksekusi pernikahan misalnya cenderung melihat perceraian secara administratif dan juridis semata. Karena hal itu kasus-kasus perceraian (dalam hal ini cerai gugat) dapat diselesaikan dalam waktu sangat singkat, tanpa upaya-upaya maksimal untuk menjaga sakralisasi (keutuhan) pernikahan. Upaya untuk menghadirkan pihak tergugat pada kasus cerai gugat misalnya terlihat sangat lemah (pasif), padahal dengan ketidak-hadiran pihak tergugat mediasi tidak dapat dilakukan. Selain itu hak-hak perempuan untuk mendapatkan nafkah paska perceraian (terutama jika membawa anak) belum mendapat perlindungan, mengingat banyaknya putusan cerai gugat yang tidak mewajibkan suami untuk memberi nafkah untuk anak yang dibawa istri. Pendekatan administratif lagi-lagi menjadi prioritas (supaya kasus cepat selesai), yang menghilangkan makna substantif yang sedianya juga diperhatikan (menjaga generasi atau anak dari ekses negatif perceraian). Keputusan cerai gugat yang menetapkan mantan suami untuk memberi nafkahpun ada kecenderungan dibiarkan tidak dilaksanakan, dengan tidak adanya mekanisme pelaksanaan putusan. 5. KESIMPULAN Cerai gugat di Kota Padang, pada kasus yang diteliti, terjadi lebih sebagai upaya perempuan memperjelas status pernikahannya setelah mengalami pengabaian oleh pihak 29 suami dalam kurun waktu cukup lama, yaitu sejak mengandung hingga anak lahir (kasus EL), bahkan hingga anak sudah dapat berlari (Fat). Yang menarik, pengabaian terjadi tidak selalu karena faktor ekonomi (untuk kasus pada pasangan terdidik dan ekonomi menengah ke atas), akan tetapi lebih sebagai simbol bahwa pihak suami sudah tidak lagi ingin meneruskan pernikahan (tradisi Minang). Keengganan suami untuk meneruskan pernikahan dipicu oleh pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang tidak selalu bersumber dari problem pada suami istri tersebut, akan tetapi juga karena adanya campur tangan atau dominasi keluarga istri atas istri yang berlebihan maupun karena campur tangan atau dominasi keluarga suami atas suami yang berlebihan pula. Pada kasus lain, keengganan muncul karena tidak tahan atas sifat istri yang temperamental, yang terjadi pada kasus istri dengan usia relatif muda dan dengan pendidikan cenderung rendah. Terkait hal itu, terdapat temuan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan muda yang ada di Kota Padang mulai melemah, dengan adanya kecenderungan pasangan suami istri mudah “menyerah” atas masalah yang dihadapi (endurens cenderung rendah) dan dengan cepat menjadikan perceraian sebagai solusi. Selain itu kurangnya pemahanan tentang keluarga diduga menjadi penyebab mengapa lembaga pernikahan tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang sakral dan perlu dijaga keberlangsungannya, yang juga dipengaruhi oleh berbagai informasi mengenai banyaknya perceraian terjadi disekitar mereka serta kasus-kasus seperti hamil sebelum nikah. Tidak tersedianya mekanisme penanaman nilai-nilai mengenai keluarga yang lebih terstruktur, sistematis dan intensif baik ditingkat keluarga, sekolah, maupun dimasyarakat, menyebabkan terjadi perubahan pemaknaan atas pernikahan bahkan perceraian. 6. DAFTAR PUSTAKA Fachrina & Aziwarti, 2006, Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer). Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Jakarta. Fachrina, 2005, Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian, Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer. Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta. Karim, Erna. 1999. Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi. Dalam Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Levinger, G. (1976) A social psychological perspective on marital dissolution, Journal of Social Issues. Levinger, George dan Moles, Oliver C., 1979. Divorce and Separation: Context, Causes, and Consequences, The Society for the Psychological Study of Social Issues, the United States of America Rodliyah, Nunung. 2011. Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi, Studi Kasus di Kota Bandar Lampung, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Disertasi, tidak diterbitkan. Saleh, K. Wantjik. 1982. Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sun Choirul Ummah, 2010. Kasus Cerai Gugat Suami Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Sleman, Yogyakartta tahun 2007-2009, Yogyakarta: Pascasarja, UIN Sunan Kalijaga. Tesis tidak diterbitkan. http://freesociologybooks.com/Sociology_Of_The_Family/12_Divorce_and_Separation.p hp http://www.fathurrizqi.com/2014/06/catatan-kecil-dibalik-tingginya-angka.html. https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-95/trends-family-transitions-formsand-functioning 30 31 PEREMPUAN MENGGUGAT: FENOMENA PERCERAIAN MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA Kustini Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Email: [email protected] Abstrak Penelitian ini difokuskan pada tiga hal: alasan istri mengajukan cerai gugat, dampak cerai gugat, serta respon struktur sosial terhadap fenomena cerai gugat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen, dan observasi. Lokasi penelitian Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi dan Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak alasan istri menggugat cerai antara lain pergeseran budaya yang semakin terbuka terutama media social, makna dan nilai perkawinan sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran serta nirtanggung jawab dari pihak laki-laki, rendahnya pemahaman agama, koordinasi dan komunikasi antarinstansi tidak berjalan, sehingga mengesankan masalah perkawinan dan perceraian sebagai dua hal yang berbeda. Ada banyak dampak negatif dari cerai gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, tetapi dalam batas tertentu memberi dampak posisif bagi perempuan karena memiliki status yang jelas serta tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri. Struktur sosial belum secara maksimal memiliki sistem untuk memperkuat tali perkawinan dan ketahanan keluarga sehingga perceraian menjadi lebih mudah terjadi. Rekomendasi penelitian antara lain agar Kementerian Agama bersinergi dengan instansi lain serta lembaga keagamaan untuk melestarikan perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian. Kata Kunci: Cerai Gugat, Perempuan, Perkawinan, Kementerian Agama, BP4. Abstract This qualitative research focused on three things: the reason of wife-initiated divorce, the impact of wife-initiated divorce, and the social structure response to its phenomenon. Research conducted by using data collection, interviews, documents study, and observation. It was conducted in Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi and Ambon. The results showed that the reasons why wife sued for divorce are: a cultural shift was getting more open especially social media, marriage meaning and values were getting lost due to neglected wife and husband`s irresponsibility, the lack of religious understanding, stagnancy of interagency`s coordination and communication. Those reasons due to the problem of marriage and divorce as two different things. There were many negative effects of wife-initiated divorce to the lives of families and childrens, even it gave a positive impact to women because her status is getting clear and she doesnt need to perform her duties as a wife. The social structure did not have yet a system for strengthening the marital relationship and family resilience so it was due to divorce becomes easier to happen. Thus, research recommendations are: The Ministry of Religious Affair should work synergycally with other institutions and religious institutions to preserve marriages and prevent divorce. Keywords: Wife-Initiated Divorce, Women, Marriage, Ministry of Religious Affairs, BP4 (Marriage Counseling, Guidance 32 1. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU tersebut sejalan dengan istilah al-Qur’an yang menyebut perkawinan sebagai mitsaqanghalizhan (perjanjian kokoh) (Anshor, 2012) untuk membangun keluarga yang disebut sakinah, mawaddah wa rahmah Sebuah keluarga dikatakan bahagia atau harmonis ketika seluruh anggota keluarga merasa tenang dan tentram, tidak ada kekerasan, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga terpenuhi dengan baik (Rofiah, 2012). Mempersiapkan kehidupan perkawinan untuk menjadi keluarga yang bahagia tidak hanya menjadi tugas dari calon pasangan. Lebih dari itu, pemerintah maupun lembagalembaga agama memiliki kewajiban untuk menyiapkan umatnya memasuki gerbang perkawinan dengan bekal yang cukup. Lembaga lembaga agama di Indonesia memiliki sistem masing-masing untuk membimbing umatnya memasuki gerbang perkawinan. Bagi komunitas Katolik, dikenal Kursus Persiapan Perkawinan (Hardana, 2013; Komisi Keluarga KWI, 2015). Sementara di kalangan komunitas muslim, program persiapan perkawinan dilaksanakan melalui Kursus Calon Pengantin. Melalui program-program tersebut, maka diharapkan pasangan akan mencapai kehidupan yang bahagia, sakinah, sukinah, atau keluarga sejahtera (Kustini, 2011; Rofiah, 2013) Meski perkawinan dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia, dalam kenyataan, banyak pasangan yang harus mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Berbeda dengan ajaran Katolik yang tidak memiliki ciri-ciri perkawinan “tak terceraikan” (Hardana, 2013), ajaran agama Islam memberi jalan keluar bagi umatnya yang tidak lagi mampu mempertahankan perkawinan melalui perceraian. Satu hal yang perlu dicatat terkait perceraian di komunitas muslim di Indonesia adalah bawa angka cerai gugat hampir selalu lebh tinggi dibanding cerai talak. Kecenderungan tingginya angka cerai gugat terjadi di tingkat nasional dan di tingkat daerah (kabupatn/kota). Pada tahun 2010-2014, dari sekitar dua juta pasangan menikah, pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama jumlahnya mencapai sekitar tiga ratus ribu lebih atau sekitar 15% lebih. Angka Perceraian (2010 -2014) 361,816 251,208 2010 276,792 2011 382,231 304,395 2012 2013 2014 Gambar 1: Jumlah Perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia (Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI, 2014) 33 Perceraian tersebut dilakukan oleh suami maupun istri dengan berbagai alasan. Dari data perceraian yang ada di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI, alasan tidak lagi ada keharmonisan menjadi angka terbesar. Kemudian alasan tidak ada tanggung jawab, alasan ekonomi, dan gangguan pihak ketiga. Data penyebab perceraian tahun 2013, adalah: a. tidak ada keharmonisan 97.615 kasus, b. tidak ada tanggung jawab 81.266 kasus, c. ekonomi 74.559 kasus, d. gangguan pihak ketiga 25.310 kasus, dan e. cemburu 9.338 kasus (Data dari Badilag MA-RI, 2014). Dari data Badilag MA tersebut, yang menarik adalah ternyata angka cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri mengalami tren naik dan lebih besar dibanding cerai talak. Perbandingan Cerai Talak & Cerai Gugat 268,381 250,360 191,013 212,595 Cerai Talak Cerai Gugat 169,673 81,535 2010 85,779 2011 91,800 2012 111,456 113,850 2013 2014 Gambar 2: Tren dan Perbandingan Cerai Talak dan Cerai Gugat (Sumber: Badan Peradilan Agama MA RI 2014) Jika dibandingkan data cerai gugat dengan cerai talak di tahun 2014, jumlah cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak, perbandingannya mencapai 70 : 30. Tingginya angka perceraian dan khususnya cerai gugat di masyarakat tentu perlu disikapi oleh pihakpihak yang selama ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan perkawinan, khususnya Kementerian Agama. Naiknya angka perceraian di satu sisi dan dominasi cerai gugat atas cerai talak yang terus terjadi di sisi lain, perlu menjadi perhatian serius, terutama setelah terjadi perubahan kebijakan yang sangat signifikan terkait dengan lembaga yang menangani perceraian. Semula Kementerian Agama mempunyai wewenang yang menyeluruh terkait perkawinan, mulai dari pengesahan perkawinan masyarakat Muslim melalui Kantor Urusan Agama (KUA), pembinaan keluarga sakinah melalui Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hingga pengesahan perceraian melalui Pengadilan Agama. Namun sejak tahun 2004, Pengadilan Agama telah dipindahkan ke Mahkamah Agung RI dan sejak tahun 2009 BP4 tidak lagi berada di dalam struktur Kementerian Agama. Dengan demikian wewenang Kementerian Agama terkait perkawinan tinggal pengesahannya saja. Fenomena tingginya angka cerai gugat menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penting diketahui mengapa tren cerai gugat di masyarakat semakin menunjukkan angka yang meningkat, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya tren tersebut, apa saja alasan-alasan dari istri sehingga mereka memutuskan melakukan cerai gugat, bagaimana peran keluarga dan kerabat dekat dan struktur sosial yang ada, dan bagaimana proses cerai gugat itu berlangsung. Hasil kajian tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam menetapkan kebijakan terkait 34 penasehatan pra nikah maupun pembinaan perkawinan secara umum. Mengingat terbatasnya kewenangan Kementerian Agama dalam memediasi perceraian, maka dibutuhkan revitalisasi dan strategi khusus dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang melakukan penasehatan dan pembinaan perkawinan. Dari pemaparan dalam latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalah penelitian yaitu: (1) Apa saja alasan-alasan dari istri sehingga memutuskan melakukan cerai gugat? (2) Apakah dampak-dampak dari cerai gugat yang dialami keluarga pasangan tersebut? (3) Bagaimana struktur sosial merespon terjadinya cerai gugat? Ada tiga tujuan dalam pnelitian ii yaitu: (1). Mengidentifikasi alasan-alasan dari pihak istri sehingga memutuskan melakukan cerai gugat. (2) Mendeskripsikan dampakdampak dari cerai gugat yang dialami keluarga pasangan tersebut. (3) Mendeskripsikan respon struktur sosial dalam peristiwa cerai gugat. Penelitian terkait fenomena cerai gugat ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama, Pengadilan Agama maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menetapkan kebijakan terkait penasehatan maupun pembinaan perkawinan. Di samping itu, lembaga lain seperti BP4 atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap program penasihatan atau bimbingan perkawinan diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini untuk menetapkan program-programnya. 2.TINJAUAN PUSTAKA Perceraian dalam Peraturan Perundangan Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan salah satu penyebab terputusnya perkawinan adalah perceraian. Dengan demikian, perceraian diakui dalam hukum peraturan perundangan. Terkait tata cara perceraian telah diatur dalam UU tersebut yaitu Pasal 39 bahwa: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Terkait teknis pengajuan pengajuan perceraian dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 40 yaitu: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa perceraian disebut talak, hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang mengendalikan talak tersebut, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. Namun demikian dalam Islam juga terdapat kasus khulu’, dimana perempuan bisa mengajukan gugat perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, maka dalam hukum perkawinan di Indonesia, dikenal adanya cerai yang diajukan oleh pisak istri ke pengadilan agama yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 disebutkan bahwa gugat perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sementara alasan-alasan perceraian disebutkan oleh UU tersebut dalam Pasal 19, yaitu a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 35 hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain. e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. f) antara suami dan istri terus menerus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada, perceraian di samping dapat dilakukan oleh suami (cerai talak) juga dapat dilakukan oleh istri (cerai gugat). Di samping tercantum dalam UU tersebut, gugat cerai juga terdapat dalam KHI Pasal 114, yang selengkapnya berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar ta’lik talak dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran ta’lik talak.” Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan inilah selanjutnya disebut sebagai curia gugat. Kajian Terdahulu Tahun 2001 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI melakukan penelitian di beberapa daerah terkait perceraian. Karim (2002) yang melakukan penelitian di Cilacap mengungkapkan data bahwa selama tahun 1996-2000 jumlah kasus cerai gugat jauh lebih banyak dibanding kasus cerai talak, berkisar antara 60 % sampai 82%. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa masih banyak tokoh agama yang berpandangan bahwa proses perceraian tidak perlu melalui Pengadilan Agama, tetapi dapat dilakukan dimanapun ketika suami menghendaki. Fenomena perceraian tidak melalui Pengadilan Agama juga ditemukan pada penelitian Kustini di Sukabumi (2000). Rumitnya struktur keluarga, akibat kepergian istri menjadi buruh migran, atau ketidaksiapan suami ditinggal istri, menjadi salah satu penyebab perkawinan maupun perceraian dilakukan secara tidak tercatat. Penelitian lain menyimpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian, suami istri harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup melalui program kursus calon pengantin (Kustini, 2011). Faktor penyebab terjadinya peceraian juga ditemukan pada penelitian Nur Rofiah dan Kustini (2013). Pernikahan usia muda karena keluarga ingin terbebas dari beban ekonomi untuk merawat anak perempuan, menjadikan pernikahan rentan berakhir dengan perceraian yang akhirnya justru menambah beban ekonomi keluarga perempuan. Definisi cerai gugat, meskipun sering dikaitkan dengan khulu’, sebetulnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu definisi menyebutkan bahwa cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali: 2009). Definisi ini tidak mengandung arti bahwa putusan cerai gugat berada di tangan suami, karena hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap (Sidang Perceraian, 2015). Definisi cerai gugat yang lebih memadai dikemukakan oleh Ahrum Hoerudin, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan 36 Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Hoerudin, 1999). Kedua definisi di atas sama-sama tidak menyebutkan soal tebusan yang dibayarkan oleh istri sebagaimana berkembang dalam definisi khulu’. Istilah cerai gugat sendiri mengalami perubahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah gugatan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 114: putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian(Fokusmedia, 2005). Demikian pula Pasal 132 KHI menjelaskan tentang gugatan perceraian sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Adapun istilah cerai gugat muncul didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menggunakan istilah cerai talak untuk permohonan talak dan cerai gugat untuk gugatan perceraian(Harahap, 2003). 3.METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 di 8 kabupaten/kota yaitu Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi, dan Ambon. Dalam laporan Badilag MA (2014) terdapat daerah-daerah yang merupakan daerah yang memiliki angka tertinggi dalam kasus cerai gugat yaitu: Jawa Timur (63.406 kasus), Jawa Tengah (54.786 kasus), Jawa Barat (51.731 kasus), Selawesi Selatan (10.003 kasus), DKI Jakarta (8.426 kasus), Sumatera Utara (7.920 kasus), Riau (7.399 kasus), dan Banten (6.582 kasus). Lokus penelitian ini adalah 8 daerah, yaitu terdiri dari 4 daerah yang merupakan daerah tertinggi angka perceraiannya berdasarkan data yang dikeluarkan Badilag MA di tahun 2014 di atas, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Di samping 4 daerah itu, ada 3 daerah lain yang ingin dikaji karena memiliki aspek budaya yang khas yaitu: Sumatera Utara (patrilineal), Sumatera Barat (matrilineal) dan Maluku (Indonesia Timur). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan dengan pertimbangan peneliti dapat mengembangkan deskripsi dan analisa mendalam dari beberapa kasus terkait dengan kasus cerai gugat.Peneliti menggunakan strategi studi kasus untuk mempelajari kasus-kasus yang terikat waktu dan tempat (Creswell, 2007). Sebagai informan utama, di setiap wilayah dipilih tiga orang perempuan yang mengalami cerai gugat dengan kriteria usia perceraian paling lama adalah tiga tahun terakhir, serta usia perkawinan ketika itu paling lama adalah lima tahun. Pada usia perkawinan itulah pasangan banyak melakukan perceraian (Eshleman, 2003) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama, yang dilengkapi wawancara dengan kerabat atau tetangga mereka, dengan tokoh masyarakat sebanyak dua orang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, dengan pimpinan lembaga yang menjadi stake holder perkawinan yaitu pejabat Kementerian Agama di kota maupun kecamatan; pejabat di Pengadilan Agama, dan Ketua BP4. 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan tiga pertanyaan penelitian tersebut, maka bisa dipaparkan secara singkat hasil penelitian sebagai berikut: Alasan Istri Menggugat Cerai Tidak mudah untuk menemukan alasan utama dan komprehensif untuk menjelaskan secara singkat mengapa isteri mengajukan cerai. Data penyebab perceraian di Pengadilan Agama sudah terpilah menjadi 14 faktor dan satu faktor lain-lain. Namun jika diteliti lebih lanjut, ternyata penyebab perceraian tidak bisa hanya dikategorikan menjadi satu faktor. Misalnya tidak ada keharmonisan sebagai salah satu faktor dominan 37 penyebab perceraian yang tercatat di Pengadilan Agamaian . Jika dikaji lebih lanjut, faktor lain penyebab perceraian seperti cemburu, tidak ada tanggung jawab atau gangguan pihak ketiga merupakan bentuk ketidakharmonisan. Karena itu, identifikasi penyebab perceraian tidak semudah sebagaimana kategori yang telah ditetapkan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan istri menggugat cerai suami ternyata tidak sederhana, bahkan sangat kompleks. Alasan itu juga tidak selalu menggunakan istilah hukum, seperti yang digunakan di Pengadilan Agama. Bahkan banyak di antara mereka, terutama dari kalangan tidak terdidik tidak mengerti istilah-istilah tersebut, yang penting bercerai, lepas bebas dari beban kehidupan. Alasan yang penting untuk ditelusuri lebih dalam. Meskipun secara nasional, sebagaimana telah dijelaskan di atas, hampir semua daerah yang diteliti juga memperlihatkan hasil yang sama, yaitu faktor tidak ada harmonis, tidak ada tanggung jawab dan ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Namun penelitian ini berhasil menggambarkan alasan-alasan lain di luar mainstream yang perlu mendapat perhatian serius. Berikut hasil temuannya. a. Aceh Cerai gugat lebih banyak disebabkan faktor perubahan dan pergeseran budaya, dan perkembangan teknologi, khususnya telepon genggam dan media sosial. Selain itu, intervensi orang tua dapat memperburuk kerentanan masa perkawinan awal karena otonomi pasangan suami istri dalam menjalani mahligai rumah tangganya tidak sepenuhnya ditangan mereka berdua. Relasi laki-laki dengan mertua yang tidak setara karena adanya dukungan ekonomi dan tempat tinggal dari pihak mertua kerapkali memosisikan laki-laki dalam situasi sulit. Kondisi ini membuat laki-laki berada di antara otoritas dirinya dalam mengelola rumah tangganya dengan kepatuhannya sebagai pihak yang mendapat penghidupan dari mertuanya. b. Padang Penyebab utama cerai gugat di Kota Padang adalah penelantaran oleh pihak suami, suami pergi tanpa kabar dan tanpa membeikan nafkah. Dalam hal ini bukan berarti suami tidak mampu secara ekonomi tetapi lebih sebagai simbol bahwa pihak suami sudah tidak lagi ingin meneruskan pernikahan (tradisi Minang yang kaya dengan simbolisasi). Keengganan suami untuk meneruskan pernikahan dipicu oleh pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang tidak selalu bersumber dari problem pada suami istri tersebut, akan tetapi juga karena adanya campur tangan atau dominasi keluarga istri atas istri yang berlebihan maupun karena campur tangan atau dominasi keluarga suami atas suami yang berlebihan pula. Pada kasus lain, keengganan muncul karena tidak tahan atas sifat istri yang temperamental terutama pada kasus istri dengan usia relatif masih muda dan dengan pendidikan cenderung rendah. Kasus lain menunjukkan bahwa istri menggugat cerai bukan karena peningkatan kemampuan ekonomi c. Cilegon Cerai gugat di Cilegon juga disebabkan oleh nusyus (durhaka), baik suami, maupun istri. Penyebab lainnya, pada kasus suami yang diteliti kebanyakan tidak pandai mengambil i’tibar dari latar belakang kehidupan istri sebelumnya, suami berwatak kikir dalam pemberian nafkah, keluarga suami terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga, ketergantungan suami kepada orangtuanya, adanya salah pengertian, salah sangka di antara suami istri, adanya kemerosotan akhlak, gagal dalam berkomunikasi dengan pasangannya, dan tidak ada yang mau mengalah d. Indramayu 38 Terjadinya cerai gugat di Indramayu lebih disebabkan beratnya permasalahan yang dihadapi istri. Sejauh istri merasa bisa mengatasi, umumnya istri akan berusaha menahan dan bersabar namun jika dirasakan tidak mampu ditanggung maka gugatan cerai merupakan keputusan terakhir. Penyebab lainnya adalah adanya pihak ketiga, yaitu keluarga yang mendukung melakukan niat bercerai, adanya asumsi bahwa kesusahan atau penderitaan psikologis setelah bercerai dirasakan akan lebih ringan dibanding meneruskan atau tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat atau teman yang pernah melakukan cerai gugat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dan proses dalam cerai gugat. e. Pekalongan Sebab utama cerai gugat di Pekalongan adalah hilangnya makna perkawinan bagi perempuan yang dipicu oleh tidak adanya tanggungjawab laki-laki, baik sebagai suami maupun ayah. Pasangan (khususnya suami) tidak cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan. Isteri yang mengajukan cerai tidak selalu memiliki latar belakang ekonomi maupun pendidikan yang cukup tinggi. Dari beberapa kasus yang ditemui, isteri yang tidak memiliki penghasilan tetap pun berani mengajukan cerai. Hal itu disebabkan isteri merasa bahwa perkawinan tidak lagi membahagiakan dirinya, suami di samping tidak memiliki pekerjaan tetap juga tidak menunjukkan tanggung jawabnya, meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang relatif lama, sampai bertahun-tahun tapa kabar Berita. f. Banyuwangi Penyebab cerai gugat untuk kasus perkawinan karena dijodohkan adalah dukungan keluarga yang sangat rendah dan kekurangsiapan suami untuk memberikan nafkah, sehingga faktor ekonomi menjadi sumber konflik, akibatnya kekerasan fisik banyak dialami perempuan. Namun ekonomi yang rendah malah menyebabkan banyak perselingkuhan dan adanya disorientasi seksual. g. Ambon Penyebab utama cerai gugat adalah lemah dan rendahnya pemahaman agama sebagai landasan perkawinan. Penyebab lainnya adalah kekerasan baik fisik maupun mental (termasuk kekerasan simbolik), serta habitus kesadaran pasca konflik yang lebih banyak memberikan pendampingan khusus kepada perempuan dan anak. Dari hasil simpulan masing-masing daerah di atas, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyebab cerai gugat tidak sesederhana istilah yang dipakai di PA, namun oleh ragam faktor. Terdapat sejumlah alasan lain yang bahkan tersembunyi dan hanya bisa diselami melalui wawancara mendalam dan pengamatan. Misalnya, soal pergeseran budaya yang semakin terbuka, terutama media sosial seperti yang terjadi di Aceh. Sementara di Padang dan Pekalongan ada situasi yang agak sama di mana makna dan nilai perkawinan sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran serta nirtanggung jawab dari pihak laki-laki. Sebetulnya hal yang sama juga terjadi di Banyuwangi, terutama perkawinan-perkawinan yang dijodohkan, dan Indramayu yang menemukan bahwa beban berat selalu ditimpakan pada pihak istri. Agak berbeda dengan Cilegon, yang salah satunya disebabkan adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, di Ambon penyebab cerai gugat lebih banyak karena rendahnya pemahaman agama para keluarga dalam memaknai lembaga perkawinan. Sehingga kekerasan baik fisik dan non fisik mendominasi perceraian. 39 Di samping itu, faktor keluarga juga menjadi penyebab lain dari perceraian. Di Aceh dan Padang, peran keluarga istri terasa dominan sehingga mengesankan ada campur tangan dan intervensi yang menyebabkan pihak suami tidak mampu meneruskan tradisi keluarga. Namun sebaliknya, di daerah lain, keluarga tidak mencoba untuk campur tangan terlalu jauh, sehingga diserahkan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Dampak Cerai Gugat Sebuah perceraian tidak pernah menyenangkan. Matriks positif dan negatif dari dampak cerai gugat menghasilkan gambaran yang seimbang. Secara negatif, perceraian menghasilkan banyak luka baik yang diterima perempuan dan anak-anaknya. Namun secara positif, mereka menganggap perceraian sebagai pintu darurat untuk membebaskan diri dari segala masalah yang sudah tidak terpecahkan lagi. Perceraian ibarat dua sisi mata uang yang dapat dimaknai secara berbeda: menyedihkan sekaligus membahagiakan. Sementara dampak kepada keluarga besar sampai saat ini dirasakan tidak terlalu besar. Berikut adalah hasil penelitian ini yang berhasil mengungkap dampak tersembunyi dari sebuah perceraian. a. Aceh Perceraian pada akhirnya berdampak pada cara pandang baru perempuan Aceh terhadap nilai dari institusi perkawinan. Kegagalan perkawinan direfleksikan sebagai sebuah proses pembelajaran diri dan pendewasaan diri. b. Padang Dampak paling kentara adalah semakin lemahnya ketahanan keluarga, terutama pada pasangan muda. Mereka kini semakin mudah “menyerah” atas masalah yang dihadapi, dan dengan cepat menjadikan perceraian sebagai solusi. Selain itu kurangnya pemahanan tentang keluarga diduga menjadi penyebab mengapa lembaga pernikahan tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang sakral dan perlu dijaga keberlangsungannya, yang juga dipengaruhi oleh berbagai informasi mengenai banyaknya perceraian terjadi disekitar mereka serta kasus-kasus seperti hamil sebelum nikah. Hal lainnya adalah tidak tersedianya mekanisme penanaman nilai-nilai mengenai keluarga yang lebih terstruktur, sistematis dan intensif baik ditingkat keluarga, sekolah, maupun dimasayrakat, menyebabkan terjadi perubahan pemaknaan atas pernikahan bahkan perceraian. c. Cilegon Dampak perceraian yang disimpulkan dari tiga kasus cerai gugat adalah kepastian status hukum sehingga mereka tidak terombang ambing dalam badai ketidakharmonisan. Dengan demikian, mereka bisa melanjutkan kehidupan baru dan terbebas dari kekerasan fisik, psikologis, finansial, seksual dan spiritual. Cara untuk menatap kehidupan yang lebih baik menguatkan perempuan untuk bisa bertahan. d. Indramayu Dampak perceraian paling berat adalah dirasakan oleh istri, terutama luka batin dan psikologis. Ada trauma berat yang dirasakan oleh para perempupuan ketika mengingat suami. Meski demikian, secara ekonomi dampaknya malah tidak begitu terasa, sebab saat ini mereka kembali bisa tinggal bersama orang tua dan bekerja. e. Pekalongan Pasca cerai gugat, isteri memiliki kepastian tentang masa depannya, status hukum yang jelas, lebih siap untuk hidup mandiri karena tidak ada harapan dinafkahi suami, serta terbebas dari perselisihan yang selama ini terjadi ketika masih dalam 40 ikatan perkawinan. Dengan demikian, perempuan bisa memulai hidup baru yang dirasaan lebih baik ketimbang hidup dalam perkawinan. Dampak negatif dari perceraian lebih berkaitan dengan kehidupan perkawinan dan keluarga yang sehat di mana pilihan itu tidak dimiliki oleh perempuan, sedangkan dampak positif adalah jika dibandingkan dengan kehidupan perkawinan dan keluarga yang tidak sehat. Dampak negatif sudah dialami perempuan ketika menjalani perkawinan tidak sehat sehingga yang tersisa adalah dampak positif. f. Banyuwangi Perempuan merasa senang ketika hakim PA mengetukkan palu, walaupun dihati ada rasa malu. Kini mereka sudah biasa mencari sendiri, sudah siap hidup mandiri atau sebagian dibantu oleh keluarga dengan menanggung anak-anaknya, terlebih kini Pemkab Banyuwangi memprogramkan pemberian anggaran kepada para korban untuk bisa hidup mandiri. g. Ambon Dampak cerai gugat tidak terlalu berat dirasakan para perempuan. Selain alasan common sense di atas, juga adanya mekanisme budaya untuk mengurangi kesedihan akibat penderitaan. Hal ini terjadi karena salah satunya prinsip kolektivitas yang menjadi dasar utama dalam membangun hubungan kekerabatan masyarakat Ambon di mana siklus suka dan duka sebagai sesuatu yang harus dihadapi, bahkan dinikmati. Dampak sebuah perceraian sebagaimana yang ditemukan peneliti (selalu) mengandung dua sisi yang berbeda. Simpulan dari penelitian ini tidak jatuh hanya pada perdebatan bahwa perceraian itu akan berdampak negatif maupun positif, namun lebih dari sekadar ini adalah bagaimana para aktor mengambil lesson learn dari perceraian yang mereka putuskan. Akhirnya adalah apakah ada kesadaran dan pengetahuan baru atau proyeksi masa depan seperti apa yang mereka harapkan. Refleksi atas peristiwa perceraian mengandung optimisme, sebagaimana perempuan Aceh memaknainya sebagai lompatan untuk menuju hidup yang lebih baik. Mereka memaknai perceraian sebagai fase yang akan membuat mereka menjadi semakin kuat dan kokoh. Mereka juga memaknai perceraian sebagai wahana pendewasan diri. Hal yang sama dapat ditemukan dari pemaknaan para perempuan di Cilegon dan Pekalongan yang karena perceraian itu bersiap diri untuk menata kehidupan yang lebih baik. Kemantapan hati ini disebabkan adanya kepastian hukum sehingga mereka tidak lagi hidup dalam ombang-ambing pengharapan yang tak berkesudahan. Bahkan di Banyuwangi, para perempuan merasa siap untuk hidup mandiri lagi. Hal lain yang dari hasil penelitian ini adalah dampak laten yang dirasakan oleh keluarga yang bercerai di Padang, terutama pasangan-pasangan muda. Mereka menganggap akibat perceraian yang semakin tinggi akan ada pelemahan terhadap ketahanan keluarga sehingga mengakibatkan lembaga perkawinan tidak menjadi sakral lagi. Misalnya, mereka semakin mudah “menyerah” atas masalah yang sebetulnya mungkin sederhana, namun dengan instan menjadikan perceraian sebagai solusi. Namun dampak perceraian yang memilukan justru tidak terlalu dirasakan di Ambon, baik oleh pasangan maupun keluarga besar, meskipun ada 1001 kisah kesedihan jika membicarakan perceraian. Situasi ini dapat terjadi karena prinsip kekerabatan yang dibangun di atas tuas kolektivitas membuat mereka memiliki mekanisme budaya untuk mengurangi beban-beban masalah. Respon Struktur Sosial terhadap Cerai Gugat Penelitian ini berhasil mengungkap respon-respon dari struktur sosial terhadap cerai gugat, bukan saja struktur formal seperti PA, KUA dan lembaga formal lainnya, tetapi 41 juga konteks sosial, karakteristik wilayah penelitian dan lembaga-lembaga adat yang masih hidup di masyarakat. Berikut kesimpulannya. a. Aceh Peran BP4 di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak menjadi rujukan utama masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah data mediasi yang dilakukan atau pihak masyarakat yang berkonsultasi di BP4 KUA. Misalnya saja di KUA Bandaraya Kota Banda Aceh dan KUA Kecamatan Baiturrahman yang memiliki peristiwa nikah hingga lebih dari 160 peristiwa nikah dalam setiap tahun, konsultasi masalah rumah tangga hanya berjumlah 7-11 kasus/tahun dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan di BP4 Kota Banda Aceh, data mediasi yang dilayani tidak terdata dengan baik karena sempat vakum selama lebih dari 10 tahun seiring dengan adanya kebijakan Negara terkait perubahan posisi BP4 di tingkat Kabupaten/Kota. Upaya mempertahankan perkawinan melalui mediasi lebih banyak dilakukan di Mahkamah Syar’iyah (MS). Namun dari data perkara perceraian yang dapat dimediasi, maka jumlah mediasi yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir adalah 95 (Tahun 2012) sampai 261 (Tahun 2014) dengan tingkat keberhasilan sangat kecil, yaitu paling sedikit hanya 1% di tahun 2012 dan 18% di tahun 2014. Sementara secara konteks sosial, meningkatnya gugat cerai di masyarakat dilihat sebagai sebuah fenomena positif, yaitu adanya kemajuan relasi laki-laki dan perempuan yang lebih setara, adanya kesadaran perempuan untuk keluar dari situasi yang tidak menguntungkan baginya, dan keterbukaan akses dan informasi. Namun yang agak disayangkan, peran adat juga belum berfungsi maksimal karena di Aceh masih hidup mediator adat yang disebut Tuha Peuet atau Keuchi’. Lembaga adat ini tidak berjalan juga karenaada kekhawatiran mengenai kerahasiaan masalah. b. Padang Respon struktur sosial terhadap cerai gugat relatif berubah ke arah yang makin objektif. Stigma negatif mengenai perceraian terutama untuk konteks kota, mulai berkurang. Masyarakat mulai melihat perceraian kasus per-kasus dalam memberi penilaian. Berdasarkan tiga kasus yang diteliti, dua kasus menunjukkan hal tersebut. Masyarakat kota yang makin kritis tidak lagi dengan serta merta memberi penilaian negatif terhadap tindakan perceraian, akan tetapi mencoba memahami lebih dalam sebelum memberikan penilaian. Hal tersebut berbeda pada masyarakat pinggiran dan tentu desa, yang masih cenderung merespon negatif kasus-kasus perceraian yang terjadi. Kondisi ini harus dicermati terutama terkait peran PA sebagai institusi yang mengeksekusi permohonan perceraian yang seolah lepas dari lembaga lain yang mengurus pernikahan (KUA), lembaga penasihatan pernikahan (BP4). Drama ini seolah memperlihatkan bahwa kehidupan berkeluarga seperti sekuel yang terpisah: pernikahan satu hal, penyelesaian masalah satu hal, dan perceraian merupakan hal yang lain. c. Cilegon Kondisi sosial masyarakat Kota Cilegon sangat berpengaruh terhadap pola perceraian yang lebih kental sebagai tindakan manusia modernitas, di mana ekonomi dijadikan satu variabel penting untuk menyelesaikan perceraian. Cilegon termasuk ke dalam kategori masyarakat semi modern yang menjadi pusat pemerintahan maupun pergerakan ekonomi. Konteks sosial inilah yang pada akhirnya banyak membentuk masyarakatnya untuk memiliki orientasi hidup yang pragmatis dan realistis. Artinya sejauh tindakannya dapat membuat ia bertahan dan hidup nikmat di dalam modernitas, ia akan tetap terjaga dan pertahankan begitu pula sebaliknya. Jika suatu perubahan dapat membuat mereka merasa sengsara, mereka akan meninggalkannya termasuk juga dengan problem keluarga. 42 d. Indramayu Secara kelembagaan, setidaknya ada empat lembaga yang memiliki tusi yang sama, yaitu BP4, KUA, Meditor di PA, dan lebe. Saat ini lembaga yang dapat dikatakan berperan dalam mengurusi perceraian di Indramayu adalah hanya lebe, yang notabene terdiri dari tokoh agama untuk membantu masyarakat mengurusi pendaftaran perkawinan maupun perceraian. Dalam kasus perceraian di Indaramayu, masyarakat umumnya menggunakan jasa lebe, sehingga lebe bisa dikatakan efektif dalam memediasi perceraian. Adapun keberadaan BP4 nampaknya belum eksis, dan hanya ‘papan nama’ di sejumlah KUA kecamatan. Bahkan untuk tingkat kabupaten, kepengurusan BP4 belum terbentuk. Sementara KUA, tidak juga berperan karena mediasi perceraian dilakukan oleh PA. Sejak saat itu, peran KUA terkait perkawinan, kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan pra-perkawinan atau kursus calon pengantin. Untuk mediasi oleh hakim di PA, selama ini kasus cerai gugat jarang ada mediasi dan kurang maksimal sebab sudah menjadi modus, jika ingin proses di PA itu segera selesai, maka pihak tergugat jangan sampai hadir, sehingga hakim bisa langsung mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut. e. Pekalongan Setelah BP4 berada di luar struktur Kemenag, maka BP4 di Kota Pekalongan secara kelembagaan sedang mengalamai transisi kelembagaan dan vakum. Sementara PA juga telah pindah dari Kemenag ke MA sehingga kordinasi antara Kemenag, BP4, dan PA sebagai stake holders perkawinan dan keluarga di Kota Pekalongan belum menemukan model kordinasi antar lembaga yang tepatsehingga bisa berperan secara maksimal dalam mempersiapkan perkawinan atau mempertahankannya. Sedangkan struktur sosial non formal perkawinan dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial yang terkait dengan perkawinan belum sepenuhnya berperan maksimal sebagai sebagai sarana pendidikan untuk membangun dan menguatkan kembali makna perkawinan. f. Banyuwangi KUA dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah tidak menyentuh permasalahan perceraian. Diperlukan terobosan peraturan yang mengatur prosedur perceraian dengan mengfungsikan peran penghulu dalam penasehatan g. Ambon Akibat regulasi, ditingkat bawah, lembaga pemerintah seperti PA dan KUA dalam merespon fenomena cerai gugat memiliki pandangan yang berbeda. PA menganggap tusi sudah sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan, sementara KUA memandangnya sebagai keterambilan tusi, terutama masalah pembinaan agama dan mediasi perceraian. Bahkan dalam setahun KUA Kota Ambon hanya memediasi enam orang, dan tak satupun yang berhasil dimediasi. Sementara lembaga adat seperti tiga batu tungku yang terdiri dari raja, imam dan tokoh, dan adalah saudara kawin tidak terlalu mendapat perhatian, bahkan seolah terabaikan, karena masyarakat inginnya instan dan langsung menuju PA. Tingginya angka cerai gugat ketimbang cerai talak bukanlah hal baru, bukan pula data mengejutkan. Masalahnya kemudian bagaimana struktur, baik formal maupun non formal meresponnya, alih-alih menindaklanjuti masalah penyebab dan akibat perceraian, sebagaimana yang sudah diuraikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa struktur formal masih belum berfungsi dengan maksimal, terutama mencegah perceraian. Selain karena regulasi yang telah ditetapkan, juga ternyata masalah koordinasi dan komunikasi antarinstansi tidak berjalan, sehingga mengesankan masalah perkawinan dan 43 perceraian sebagai dua hal yang berbeda. Ada parsialisme dalam menangani dua hal ini, seperti sekuel drama. Padahal membicarakan perceraian juga secara intersepsi membincangkan perkawinan. Akibatnya, fungsi KUA, BP4 dan lembaga Suscatin tidak berjalan dengan maksimal, sementara di pihak lain, PA adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan perceraian. Berkelindan dengan lemahnya struktur formal, struktur non-formal seperti pranata sosial juga belum berfungsi. Padahal di tiap daerah yang diteliti memiliki kekuatan berupa kearifan-kearfian lokal, seperti di Aceh terdapat mediator adat yang disebut Tuha Peuet atau Keuchi’, di Indramayu ada lebe, serta tiga batu tungku dan saudara kawin di Ambon. Analisis Cerai gugat merupakan peristiwa yang terkait dengan sebuah relasi khususnya antara suami isteri. Fenomena cerai gugat dapat dianalisis melalui tiga teori berikut ini. Pertama, adalah teori pertukaran sosial (social exchange theory). Teori ini memandang bahwa hubungan interpersonal dilandasi oleh harapan memperoleh imbalan dari adanya hubungan tersebut. Perkawinan adalah hubungan interpersonal antara suami dan istri yang dibangun di atas harapan masing-masing pihak. Kedua, adalah teori pilihan sosial (social choice theory). Teori ini mempunyai ide dasar bahwa orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan (Coleman, 1990). Ketiga, teori ketidakadilan gender (gender injusttice). Menurut teori ini, hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stigmatisasi, kekerasan, dan multi beban. Secara umum perceraian (dalam hal ini cerai gugat) terjadi karena perempuan merasa tidak puas dengan kondisi kehidupan perkawinanya. Namun sesungguhnya alasan perceraian lebih dari sekedar tidak adanya kepuasan. Dengan menggunakan teori trade off (Collins & Coltrane, 1992), perkawinan dilihat sebagai satu jenis trade off antara berbagai sumber daya seperti pendapatan, cinta, pekerjaan domestic, dan kehidupan seksual. Ketika satu hal berkurangm misalnya ekonomi, perkawinan akan tetap langgeng jika hal lain, misalnya cinta kasih, tetap terjaga dalam perkawinan. Melalui teori pertukaran sosial, relasi perkawinan yang berakhir dengan cerai gugat mengindikasikan bahwa istri tidak lagi merasa memperoleh kebahagiaan (reward), dan lebih banyak mengalami kesulitan atau penderitaan (social cost). Jika perempuan merasa puas dan nyaman, ia tidak akan meninggalkan kehidupan perkawinannya (Scanzoni & Scanzoni, 1981). Menurut teori pertukaran social (exchange theory) setiap pasangan melihat kehidupan perkawinan dalam dua tahapan. Pertama, pasanganmembandingkankeuntunganrelatif dalam perkawinan. Jika salah satu atau keduanya merasa hanya sedikit mendapatkan keuntungan, maka kepuasanperkawinanpasanganakanmenjadi rendah, sehingga memilih hidup tanpa perkawinan menjadi salah satu pilihan. Dalam kondisi seperti ini perceraian dianggap sebagai alternatif. Pada tingkatan kedua, pasanganmembandingkan kebahagiaan dan kesulitanketika berelasi dalam perkawinan. Dalam tahapan tertentu ia merasa lebih menguntungkan jika hidup selain dalam pernikahan, misalnyamenjadi lajangkembali melalui perceraian (Klein and White, 1996). Cerai Gugat mengindikasikan seorang istri tidak mendapatkan manfaat dari perkawinannya. Dalam perspektif teologis dan yuridis, hilangnya makna perkawinan dapat dijelaskan bahwa sakinah (ketenteraman) dalam istilah al-Qur’an dan kebahagiaan lahir batin dalam istilah Undang-Undang Perkawinan sebagai tujuan perkawinan gagal dicapai. Tidak adanya tanggungjawab (qiwamah) seorang menjadi sangat krusial karena masyarakat Muslim meyakini bahwa dalam keluarga, suami mempunyai peran sebagai penanggungjawab keluarga (Qawwam). Quraish Shihab menjelaskan bahwa Qa’im adalah 44 istilah untuk orang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya, sedangkan Qawwam disematkan pada orang yang melaksanakan tugas tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang (Shihab, 2009). Laki-laki disebut Qawwam oleh an-Nisa/4:34 berarti bahwa mereka adalah orang yang semestinya melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab keluarga sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa hilangnya makna perkawinan sebagai salah satu faktor perceraian, sejalan dengan temuan penelitian Ranga and Sekhar (2002) di India yang berjudul Divorce: Process and Correlates: A Cross-Cutural Study. Penelitian ini menunjukkan para istri yang mengajukan cerai tidak terbatas pada mereka yang memiliki pendidikan atau pekerjaan yang mapan. Meskipun secara sosial perempuan India berada pada posisi tidak terdidik atau buta huruf dan sulit memperoleh lapangan kerja, mereka tetap memilih bercerai karena problem yang dihadapi dalam perkawinan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sementara itu, Eshleman (2003) melihat perceraian dilihat dari tingkatan social ekonomi, terjadi pada semua level. Namun demikian, menurut Eshleman jika faktor pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan digunakan untuk mengukur indeks sosial ekonomi, maka perceraian terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkal social ekonomi rendah. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian di Pekalongan maupun di Aceh. Seorang istri di samping tidak memperoleh harapan yang ditumpukan pada suami melalui perkawinannya, mereka juga mengalami beberapa bentuk ketidakadilan gender, meliputi marginalisasi (proses pemiskinan bagi kaum perempuan), subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotype dan diskriminasi, pelabelan negatif, kekerasan, bekerja lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 1997). Misalnya suami yang tidak menafkahi istri, bahkan dinafkahi istri, tetapi kemudian ia selingkuh atau bahkan kawin lagi. Istri dalam hal ini mengalami marginalisasi dalam bentuk tidak dilibatkan atas keputusan suami untuk menikah lagi, subordinasi dalam bentuk perasaan sakit hatinya dianggap tidak penting, pelabelan negatif dalam bentuk dipandang tidak becus sebagai istri sehingga suami mencari istri lagi, kekerasan dalam bentuk kekerasan psikologis, dan beban ganda karena ia menjalani fungsi sebagai ibu sekaligus ayah. Cerai gugat sebagaimana cerai talak menyebabkan banyak perempuan akhirnya berperan sebagai orangtua tunggal, padahal sejak kecil tidak disiapkan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Ketika diharuskan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah tunggal, perempuan menjadi rentan untuk mendapatkan pekerjaan dengan risiko tinggi, bahkan menjadi korban perdagangan perempuan. Di samping itu, cerai gugat juga menyebabkan anak tumbuh tanpa figur ayah sebagai teladan yang mengakibatkan anak mengalami kebingungan ketika tumbuh menjadi remaja. Sayangnya, meskipun tidak adanya tanggungjawab menjadi faktor dominan penyebab cerai gugat, namun struktur sosial formal perkawinan seperti KUA, BP4, dan Pengadilan Agama justru sedang berada dalam masa pencarian sistem koordinasi yang efektif. Sementara itu, tokoh agama dan masyarakat serta lembaga yang bisa menjadi stake holder perkawinan pun masih memerlukan dukungan agar bisa memanfaatkan forum-forum sosial sebagai sarana pendidikan tentang perkawinan dan keluarga yang sakinah bagi seluruh anggota keluarga, yakni suami, istri, dan anak-anak sesuai perkembangan zaman. 5.KESIMPULAN Memutuskan ikatan perkawinan melalui cerai gugat bukanlah pilihan yang menyenangkan, baik bagi istri, suami, maupun anak-anak. Pengalaman hidup yang penuh dengan pergulatan batin yang cukup lama, serta mempertimbangkan banyak hal (reward dan cost), akhirnya perempuan “berani” untuk menggugat cerai. Sebab utama cerai gugat 45 antara lain ketidaksiapan pasangan memasuki kehidupan berkeluarga sehingga nilai sacral perkawinan tidak lagi ditemukan. Hilangnya makna perkawinan bagi perempuan yang dipicu oleh tidak adanya tanggungjawab laki-laki, baik sebagai suami maupun ayah. Pasangan (khususnya suami) tidak cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan ikatan perkawinan. Sebab lainnya cukup beragam seperti faktor budaya yaitu intervensi keluarga besar maupun faktor eksternal ikut memperkuat perempuan mengambil inisiatif untuk bercerai misalnya perkembangan teknologi. Perceraian, dalam hal ini cerai gugat memberi dampak positif maupun negatif bagi perempuan. Stigma sebagai “janda” dengan segala risikonya harus dialami perempuan. Ia juga harus berperan sebagai kepala keluarga dan orang tua tunggal. Namun pasca cerai gugat istri memiliki kepastian tentang masa depannya, status hukum yang jelas, lebih siap untuk hidup mandiri karena tidak ada harapan dinafkahi suami, serta terbebas dari persei gugat, perselisihan yang selama ini terjadi ketika masih dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, perempuan bisa memulai hidup baru yang dirasaan lebih baik ketimbang hidup dalam perkawinan. Struktur sosial formal perkawinan dalam hal ini KUA, BP4, dan Pengadilan Agama sedang dalam pencarian model kordinasi terkait pelestarian lembaga perkawinan. Sedangkan BP4 dalam kondisi vakum, dan secara kelembagaan Pengadilan Agama juga tengah berada dalam masa penyesuaian setelah berada di bawah Mahkamah Agung. Kondisi ini menyebabkan lembaga stake holders perkawinan tidak bisa berperan secara maksimal dalam mempersiapkan perkawinan atau mempertahankannya. Sedangkan struktur sosial non formal perkawinan dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial terkait belum sepenuhnya berperan maksimal sebagai sebagai sarana pendidikan untuk membangun dan menguatkan kembali makna perkawinan.. Rekomendasi Beberapa upaya untuk mempertahankan makna perkawinan yang selaras dengan perkembangan zaman perlu dilakukan, baik pada masa pra perkawinan, selama perkawinan, maupun ketika perkawinan diujung tanduk. Relasi suami istri dengan pola partnership lebih memungkinkan bertahan daripada pola atasan dan bawahan. Dalam relasi partnership memungkinkan suami-istri dan orangtua-anak untuk bertukar peran secara fleksibel. Pola relasi atasan dan bawahan menjadi sangat riskan ketika suami yang didudukkan sebagai atasan tidak mampu memenuhi kewajibannya namun tetap mempertahankan otoritasnya. Pola partnership atau equal partner (Scanzoni & Scanzoni, 1981) dalam perkawinan dan keluarga bisa ditanamkan secara terus menerus oleh para tokoh agama dalam beragam pengajian dan secara terstruktur dapat disampaikan dalam Kursus Calon Pengantin. Kursus ini mempunyai nilai strategis karena diberikan tepat ketika pasangan akan atau baru memasuki gerbang rumah tangga sehingga perlu dirancang model, modul, dan modalnya. Lembaga BP4 menjadi penting untuk dikuatkan karena menjadi lembaga yang paling relevan untuk mengemban misi pelestarian perkawinan. Kekosongan fungsi BP4 karena sedang dalam proses reposisi, memperlebar problem perkawinan karena minimnya lembagi konsultasi dan mediasi perkawinan. Suscatin yang hanya dilakukan sebelum pernikahan, dan cenderung formalitas, tidak mampu menyelesaikan problem keluarga yang semakin kompleks. Pemerintah daerah sudah semestinya memandang naiknya angka perceraian dan dominasi cerai gugat sebagai masalah serius dan bersedia memperkuat BP4 misalnya dari segi pendanaan. Dengan dukungan Pemda, BP4 dapat lebih leluasa bergerak dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di daerah tersebut dalam upaya pelestarian perkawinan. 46 Pasangan suami-istri yang sudah sampai ke PA pada umumnya adalah mereka yang sudah tidak mampu mengatasi masalah perkawinannya. Dalam kondisi seperti ini, maka proses mediasi menjadi sangat penting untuk dilakukan secara lebih intensif dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih mungkin dilakukan oleh mediator non hakim. BP4 dapat membantu Pengadilan Agama untuk memperbanyak mediator non hakim bersertifikat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan mengingat terbatasnya jumlah hakim dan meluasnya wewenang Pengadilan Agama setelah pindah ke Mahkamah Agung. Pemerintah Daerah dapat memainkan peran secara maksimal dengan memberikan layanan terpadu perkawinan dan keluarga yang melibatkan seluruh stake holder yang ada di wilayah tersebut. Layanan perkawinan dan keluarga satu pintu ini dapat memberikan layanan informasi dan pendidikan pra perkawinan, layanan administrasi hingga resepsi perkawinan, layanan penasehatan dan mediasi selama masa perkawinan, sehingga pasangan suami istri yang menginjakkan kaki ke Pengadilan Agama telah dipastikan sebagai pasangan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan perkawinannya. 6.DAFTAR PUSTAKA Anshor, Maria Ulfah.2012. Kompilasi Hukum Islam yang Ramah terhadap Perempuan:. Dalam Jurnal Perempuan Nomor 73 Tahun 2012 “Perkawinan dan Keluarga”, April 2012, h. 19-30. Ali, Zainuddin. 2009. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Creswell. John W. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches, London: Sage Publications. Collins, Randall & Coltrane, Scott. 1992. Sociology of marriage and the family: Gender,love and property. (3rd ed.). Chicago. Nelson-Hall Inc. Eshleman, J. Ross. 2003. The family. 10th Edition. New York: Pearson Education Inc. Fakih, Mansour. 2007. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustakan Pelajar. Fokusmedia. 2005. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung. Gelles, Richard J. 1995. Contemporary Families A Sociological View. California. Sage Publications. Harahap, Yahya. 2003. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-2. Ketut Hardana, Timotius I Ketut Adi. 2013. Kursus Persiaan Perkawinan. Jakarta. Yayasan Obor. Herien, Puspitawati. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, Bogor. PT IPB Press. Hoerudin, Ahrum. 1999. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Bandung: PT. Aditya Bakti. Kesindo Utama, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, h. 235 Khairunnida, Daan Dini. 2013. Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Hasil Penelitian di 6 Wilayah.Jakarta. Kerjasama Rahima, BP4, UNFPA, dan KPPPA. Klein, David M. White, James M. 1996. Family Theories An Introduction, California: SAGE Publications. 47 Komisi Keluarga KWI. 2015. Panduan pelaksanaan kursus persiapan perkawinan Katolik. Jakarta. Obor. Kustini. 2002. Perceraian di Kalangan Buruh Migran Perempuan: Studi Kasus di Desa Kadupura, Kecamatan Cibodas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Tesis pada Program Pascasarjana Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Kustini. 2011. Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Rofiah, Nur. dkk. 2013. Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Rofiah, Nur dan Kustini. Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur, Dalam Jurnal Harmoni Vol. 13 Nomor 1 Mei – Agustus 2014, h. 146 158. Rangan, Rao ABSV. Sekhar K. 2002. Divorce: Process and Correlates: A Cross-Cultural Study, Journal of Comparative Family Studies, Autum 2002: 33, 4, ProQuest, h. 557. Scanzoni, Letha Dawson.dan Scanzoni John. 1981. Men, Women, and Change: A Sociology of Marriage and Family. New York. Mc.Graw Hill. 48 RESISTENSI DAN PRAKTIK KUASA PENGETAHUAN PEREMPUAN PETANI PADI SAWAH LEBAK DALAM PEMENUHAN PANGAN KELUARGA Yunindyawati Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya Jln Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Email: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistensi perempuan atas marjinalisasi pada proses pertanian padi dan praktik kuasa pengetahuan dan praktik kuasa penetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan resistensi perempuan berupa resistensi langsung di dalam proses pertanian padi, dan resistensi tidak langsung dengan melakukan diversifikasi pekerjaan di luar sektor pertanian padi. Dengan demikian maka perempuan tetap bisa mempraktikkan kuasa pengetahuan yang dimiliki sehingga bisa berkontribusi dalam pemenuhan pangan keluarga. Kata Kunci: Resistensi, Marjinalisasi, Perempuan, Pangan, Keluarga Petani Abstract This research was to analize resistance of women over marjinalization of agriculture process and the parctice of power of woman’s knowledge in the fullfilment family food. The qualitative methode and critical paradigm were used in this research. The data carried out by in depth interview technique, observation and Focus Group Discussion (FGD). The result showed that the woman’s resistance pattern were direct resistance and indirect resitance by doing work in the off farm sector. So woman practiced the power of knowledge and then they could contribute in fullfilment food family Keywords: Resistance, Marjinalization, Woman, Food, Family, Farmer 1.PENDAHULUAN Perempuan memiliki peran cukup signifikan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Moussa 2011, Sukiyono et al. 2008).Di bidang pertanian dan pedesaan perempuan bukan hanya memproduksi dan mengolah hasil pertanian tetapi juga berperan penting dalam distribusi pemasaran.Kontribusi perempuan semakin terlihat ketika mereka memainkan peran domestik sekaligus melakukan aktivitas produksi pertanian. Peranan perempuan dalam produksi pertanian adalah penting dalam menentukan status nutrisi rumah tangga dan juga sumbangan mereka dalam pendapatan rumah tangga. Studi yang dilakukan Sukiyono dan Sriyati (1997) menemukan bahwa konstribusi perempuan transmigran berdagang sayuran sebesar 45% dari total pendapatan rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan selain dalam produksi pertanian, perempuan juga menyumbang ekonomi keluarga melalui sektor perdagangan. 49 Selain itu, secara sosial perempuan dikonstruksikan bertanggung jawab atas kebutuhan konsumsi pangan keluarga terkait nutrisi anggota keluarga.Mereka memegang peran kunci seperti dalam penyediaan air bersih, mengatur pola makan, jenis makanan dan hal-hal lain berkaitan dengan konsumsi keluarga. Tanpa terpenuhi kebutuhan pangan keluarga, para laki-laki tidak akan mampu bekerja di sawah/lahan mereka. Hal ini menunjukkan peran perempuan cukup sentral dalam ketahanan pangan keluarga. Selain itu, kesalahan dalam proses pengolahan dan penyiapan pangan di tingkat keluarga akan menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas gizi pangan, dan pada akhirnya menurunkan ketahanan pangan. Secara universal, peran gender untuk perempuan dan laki-laki diklasifikasikan dalam tiga peran pokok yaitu peran reproduktif (domestik), peran produktif (publik) dan peran sosial (masyarakat). Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani dan tugas kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Peran produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.Peran masyarakat terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik (Hubeis 2010). Dalam sebuah keluarga, terdapat suami, istri dan anak.Masing-masing individu memiliki status dan peran yang dilekatkan dan dijalankan.Untuk mengatur hubungan antara mereka masuklah kelembagaan-kelembagaan dalam keluarga. Kelembagaan inilah yang akan mengatur interaksi dan hubungan antara anggota keluarga. Sebagai contoh kelembagaan perkawinan, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kelembagaan pangan dalam sebuah keluarga biasanya memuat nilai-nilai dan aturan main yang dijalankan untuk menjaga kecukupan, stabilitas, aksesibilitas dan kualitas pangan. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi FAO, terdapat 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan (LIPI 2005) yaitu: 1. Kecukupan ketersediaan pangan 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun 3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta 4. Kualitas/keamanan pangan Dari keempat aspek tersebut secara gender, perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memainkan peran menuju ketahanan pangan keluarga. Persoalannya adalah konstruksi sosial masyarakat melihat bahwa persoalan pangan keluarga adalah tanggung jawab perempuan. Umumnya perempuan diperankan sebagai aktor yang bertanggungjawab atas pangan keluarga. Mulai dari penyediaan makanan sehat dan bergizi, pola pengasuhan gizi keluarga bahkan termasuk pada proses produksi pangan keluarga sehingga tetap tersedia, terjangkau dan stabil keberadaannya dalam keluarga. Dilihat dari hal tersebut secara sekilas terdapat dugaan bahwa peran perempuan relatif tinggi. Peran perempuan yang relatif tinggi dalam pemenuhan pangan keluarga ini tidak diimbangi dan didukung oleh kebijakan yang berpihak pada perempuan. Pada kasus perempuan petani padi sawah lebak di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, kebijakan pertanian terutama peningkatan produktivitas padi dengan penerapan revolusi hijau dan program pertanian yang menyertainya justru memarjinalkan peran perempuan. Kuasa pengetahuan perempuan dalam bercocok tanam padi tergusur oleh teknologi dan inovasi pertanian, meskipun demikian perempuan mencari bentuk lain sebagai praktik atas 50 kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga, diantaranya melakukan diversifikasi pekerjaan. Praktik-praktik kuasa pengetahuan perempuan pada aspek di luar sektor pertanian padi sawah lebak sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan atas tertutupnya peluang praktik kuasa pengetahuan perempuan di sektor pertanian padi sawah lebak. Bentuk-bentuk perlawanan kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga petani padi sawah lebak menjadi menarik dikaji lebih lanjut. Tujuan penelitian ini menganalisis resistensi perempuan atas marjinalisasi peran perempuan di sektor pertanian padi sawah lebak dan praktik kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga petani padi sawah lebak di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir. 2.METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 11 informan dan 9 keluarga sebagai subyek kasus penelitian.Subyek kasus dalam penelitian ini adalah keluarga petani padi sawah lebak, yakni suami, istri dan anak. Informan penelitian ini adalah kepala desa, ketua PKK, ketua KUBE, ketua kelompok tani, petugas kesehtan, tokoh adat dan tokoh agama.Observasi dan diskusi kelompokdilakukan untuk memperdalam data yang diperoleh serta validasi data dari para informan dan subyek kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif, data dikategorikan dalam satuan uraian, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan.Lokasi penelitian di desa Ulak Aurstanding di kecamatan Pemulutan Selatan kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. 3.TEMUAN DAN PEMBAHASAN Proses transformasi pertanian, dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang diintrodusir pemerintah (terutama setelah penerapan revolusi hijau) membawa dampak marjinalisasi peran perempuan. Peran perempuan padapertanian tradisional sangat tampak terutama pada kegiatan ritual dalam proses pertanian (sebelum, panen, saat panen dan setelah panen) padi sawah lebak. Marjinalisasi peran perempuan di sektor pertanian padi sawah lebak melahirkan resistensi terhadap proses pertanian yang diintrodusir oleh pemerintah. Resistensi merupakan sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan dan menentang. Bentuk resistensi terhadap proses pertanian yang dilakukan perempuan meliputi resistensi atas benih unggul, resistensi atas penggunaan herbisida dan resistensi atas teknologi pendukung pertanian. Resistensi atas penggunaan bibit unggul yang menggantikan bibit lokal tradisional pegagan dilakukan dengan cara; perempuan tetap menggunakan bibit pegagan untuk menanam padi meskipun hanya segelintir orang yang melakukannya. Secara umum, bibit yang ditanam petani padi sawah lebak (saat ini) telah berganti ke bibit unggul yang diintrodusir pemerintah melauli kebijakan revolusi hijau. Pada titik ini, pada persoalan bibit telah terjadi perampasan kuasa pengetahuan perempuan untuk memilih dan memilah bibit yang layak ditanam, namun masih ada perempuan yang tetap menggunakan bibit lokal pegagan. Pada saat penelitian berlangsung (tahun 2012) dimana terjadi gagal panen di Kabupaten Ogan Ilir), justru benih padi lokal (padi tinggi) yang bisa bertahan sehingga tidak gagal panen. Namun jumlah petani yang menanam padi lokal sangat sedikit, hanya sebagai pemenuhan ketersediaan pangan keluarga dan bukan untuk dijual. Resistensi atas penggunaan herbisida dilakukan perempuan dengan tetap membersihkan rumput (rencam) secara manual. Kegiatan rencam masih banyak dilakukan di kalangan petani perempuan sebagai upaya perlawanan atas penggunaan herbisida. Penggunaan herbisida dirasakan merugikan secara ekonomi karena harus mengeluarkan uang untuk membeli racun rumput (sebutan herbisida oleh komunitas petani padi). Dengan 51 membersihkan secara manual maka petani lebih bisa berhemat serta memberi peluang bagi keterlibatan peran perempuan. Pada titik ini, intervensi pengetahuan pemerintah dalam membersihkan rumput menggunakan herbisida tidak sampai merampas kuasa pengetahuan perempuan tetapi hanya menggusurnya dari proses pertanian padi sawah lebak. Resistensi atas penggunaan teknologi pertanian seperti mesin grentek, perontok padi, sabit dan pembajak sawah (traktor) yang didominasi laki-laki dilakukan dengan cara perempuan berusaha untuk bisa menggunakan alat-alat pertanian tersebut meskipun tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Perempuan melawan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai obyek dari program pertanian. Perlawanan ini membuahkan hasil dimana terdapat perempuan yang bisa mengoperasikan alat-alat pertanian modern (meskipun jumlahnya sedikit). Bentuk-bentuk resistensi yang dikemukakan diatas adalah resistensi langsung atas marjinalisasi kuasa pengetahuan perempuan dalam proses produksi padi sawah lebak. Selain resistensi langsung atas marjinalisasi di sektor pertanian padi sawah lebak, resisten perempuan juga dilakukan dalam bentuk tidak langsung dengan melakukan diversifikasi pekerjaan diluar sektor pertanian padi, yakni pekerjaan tani non padi dan usaha non pertanian. Diversifikasi pekerjaan menjadi bentuk resistensi simbolik atas tergusurnya peran perempuan dari sektor pertanian padi. Perempuan menunjukkan bahwa meskipun mereka termarjinalkan dalam proses pertanian padi sawah lebak untuk pemenuhan pangan keluarga, mereka tetap bisa berkontribusi dengan melakukan pekerjaan tani non padi seperti menanan sayur mayur dan kacang-kacangan di sekitar rumahnya dan pekerjaan non tani dengan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendapatkan uang seperti menenun songket, menyiang ikan, membuat atap daun dan berjualan makanan. Diversifikasi pekerjaan perempuan menjadi simbol perlawanan tidak langsung, artinya tidak berhubungan dengan proses produksi padi sawah lebak. Perlawanan simbolik untuk menunjukkan bahwa perempuan dan pangan memang tidak bisa dipisahkan, selalu berhubungan dalam pemenuhan pangan keluarga. Diversifikasi pekerjaan perempuan semakin terlihat setelah tergusurnya peran perempuan karena intervensi revolusi hijau. Pada saat perempuan terlibat pada seluruh proses pertanian padi lebak (sebelum penerapan revolusi hijau) belum banyak variasi jenis pekerjaan perempuan, karena waktu mereka banyak dihabiskan untuk produksi padi sawah lebak. Pekerjaan mengumpulkan bahan pangan dari ekologi rawa telah dilakukan sejak dahulu namun seiring marjinalisasi peran perempuan, pekerjaan mengumpulkan bahan pangan dari rawa semakin banyak dilakukan. Begitu juga dengan kerajinan tenun songket, dimana komunitas petani padi sawah lebak baru mencoba kerajinan tenun songket pada tahun 1992, seiring masuknya revolusi hijau di komunitas petani padi sawah lebak. Hal ini menunjukkan perempuan tetap kreatif untuk memberikan kontribusinya bagi pemenuhan pangan keluarga. Kreatifitas perempuan dalam pemenuhan pangan sesungguhnya bukan hanya karena sebagai bentuk perlawanan atas marjinalisasi pada proses pertanian padi lebak tetapi juga disebabkan oleh tekanan ekonomi keluarga yang menuntut terpenuhinya kebutuhan keluarga. Diversifikasi pekerjaan tani non padi: resistensi atas marginalisasi kuasa pengetahuan perempuan di sektor pertanian padi sawah lebak dan ujung tombak bagi pemenuhan pangan keluarga. Perempuan petani padi sawah lebak di desa Ulak Aurstanding melakukan diversifikasi pekerjaan tani non padi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pekerjaan tani non padi tersebut antara lain; mengumpulkan bahan pangan dari ekologi rawa lebak. Hilangnya kontribusi kuasa pengetahuan perempuan di bidang pertanian padi sawah lebak, tidak menyurutkan perempuan untuk tetap berperan bagi pemenuhan pangan keluarga. Hal ini dilakukan bukan hanya karena persoalan kebutuhan pangan keluarga 52 namun merupakan bentuk resistensi mereka untuk tetap memiliki kuasa pengetahuan dalam pemenuhan pangan keluarga. Para petani dan perempuan petani padi sawah lebak menyadari bahwa sejak masuknya revolusi hijau terjadi peningkatan produktifitas padi, namun juga memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap sarana produksi pertanian. Ketika terjadi gagal panen maka kerugian yang dialami juga besar, yang berakibat pada hutang petani membengkak. Diversifikasi pekerjaan tani non padi menjadi sangat penting dilakukan oleh keluarga petani jika menginginkan mereka tetap bisa makan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Pertanian padi sawah lebak sangat rentan dipengaruhi musim memaksa petani melakukan strategi nafkah demi terpenuhinya pangan keluarga. Kondisi inilah yang menjadi pemicu bagi para petani khususnya perempuan petani padi sawah lebak yang telah tergusur perannya, melakukan diversifikasi pekerjaan tani non padi sebagai penopang bagi terpenuhinya pangan keluarga. Oleh karenanya diversifikasi pekerjaan tani non padi menjadi suatu keharusan untuk melawan marginalisasi perempuan petani pada proses pertanian padi sawah lebak dan juga sebagai ujung tombak bagi pemenuhan pangan keluarga. Kuasa pengetahuan perempuan dalam memenuhi ketersediaan pangan keluarga petani padi sawah dipraktikkan dengan mencari dan mendapatkan bahan pangan dari lingkungan sekitar. Usaha-usaha perempuan memperoleh pangan dari ekologi rawa sesungguhnya membuktikan betapa perempuan dan alam memiliki hubungan erat. Perempuan mampu memilih bahan pangan rawa yang aman dikonsumsi keluarga, namun tidak mengeskploitasi untuk kepentingan ekonomis. Perempuan mengambil bahan pangan dari ekologi rawa secukupnya untuk memenuhi konsumsi keluarga. Oleh karena tidak ada unsur eksploitasi terhadap alam, sehingga ekologi rawa tetap terjaga keberlanjutannya (sustainability). Maria Mies dalam Shiva 1997, menyatakan kegiatan perempuan dalam menyediakan pangan pangan sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengkonsumsi apa yang tumbuh di alam, tetapi mereka membuat segala sesuatu menjadi tumbuh. Proses pertumbuhan secara organis yang di dalamnya perempuan dan alam bekerjasama sebagai mitra telah menciptakan suatu hubungan khusus antara perempuan dan alam. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian padi sawah lebak masih dijumpai hingga saat ini, meskipun sangat jauh berbeda kontribusi perempuan pada saat sebelum penerapan revolusi hijau dan setelahpenerapan revolusi hijau. Revolusi hijau telah mereduksi, menggusur dan memarginalisasi peran perempuan petani padi sawah lebak. Shiva 1997, bahkan menyebutkan revolusi hijau merupakan proses dominasi dan kekuasaan budaya yang menggusur ideologi budaya dan politik perempuan Selatan (negara berkembang). Pada masa sebelum revolusi hijau perempuan memiliki peran dihampir seluruh proses pertanian padi sawah lebak. Mulai dari penyiapan lahan, pemilihan bibit, hingga ke proses pemanenan. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan bibit diungkapkan (Jasiyah 50 th) sebagai berikut: “Bibitnye sendiri, kalu guleh taun ini dibuat bibit lagi, ibu yang buatnye, yang nyemaikan….akuni bapaknye lak meninggal. Anakku yang bujang due bantu kesawah. (Bibit yang disemai bibit sendiri yang dipilih dari hasil padi yang didapat. Ibu yang membuatnya, menyemaikan, karena bapak sudah meningggal. Selain itu dibantu juga oleh dua orang anak laki-laki) Para perempuan menyisakan padi untuk dijadikan bibit, segera setelah panen usai. Perempuan memilih dan memilah padi yang diperkirakan bagus untuk ditanam kembali. 53 Biasanya mereka memilih padi yang bagus dengan cara menampi, menggunakan alat tampir dari bambu,dengan digoyang-goyangkan akan terpisah antara padi yang bernas dan padi yang tidak berisi. Kemungkinan tumbuh yang ditampi (padi bernas) cukup tinggi jika dibandingkan dengan padi yang tidak ditampi.Padi ini kemudian disemai dengan cara ditugal, ditanam dengan menggunakan alu dari batang kayu.Setelah tumbuh agak tinggi dan air rawa surut,kemudianbibit padi dipindahkan ke lahan pertanian. Kuasa pengetahuan perempuan dalam memilih bibit lokal ini kemudian digantikan dengan bibit unggul yang diintrodusir oleh pemerintah. Pemerintah mengganti bibit padi lokal Pegagan dengan IR 42, Ciherang dan INPARA 1-13. Bibit dari pemerintah disebut sebagai bibit unggul dan ajaib karena waktu tanam hingga panen lebih cepat dan produktivitas lebih tinggi, sementara bibit tradisional komunitas yakni pegagan dianggap sebagai bibit primitif. Kuasa pengetahuan perempuan memilih dan memilah padi untuk menghasilkan bibit unggul mau tak mau tergusur dan kehilangan kesempatan untuk dipraktikkan. Pada titik ini, revolusi hijau telah merampas hak perempuan memproduksi bibit lokal. Perempuan juga terlibat dalam persiapan lahan dan menyemaikan padi, bahkan sebagian besar pekerjaan pertanian dilakukan oleh perempuan, kecuali pekerjaan yang berat. Berikut penuturan Maimuna (50 th): “Kalu nugal atau buat anak padi biasenye ibu-ibu, ngambil mindahkan ibuibu, yang mikul-mikul untuk mindahke kesawah bapak. Merumput gotong royong bapak ibu, kalu banyak rumput ibu, kalu dikit rumput bapak” Pada saat air yang menggenangi lahan rawa agak surut, maka ditemui banyak rumput sisa tumbuhan dan rumput yang tumbuh selama air pasang (tumbuhan rawa). Oleh karena itu perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditanami.Mayoritas perempuan terlibat dalam kegiatan ini. Secara manual mereka membersihkan rumput tersebut menggunakan tangan dan sabit, namun setelah revolusi hijau dan dikenalkan dengan racun rumput, mereka menggunakan obat tersebut (jika memiliki kecukupan uang untuk membeli dan jika tidak maka dilakukan secara manual). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan herbisida mengurangi peran perempuan dalam proses pertanian padi sawah lebak. Herbisida merupakan racun membunuh rumput, yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk memudahkan membasmi rumput, namun di sisi lain mengurangi keterlibatan perempuan petani padi sawah lebak. Setelah lahan bersih dari rumput maka para perempuan mengambil padi yang sudah ditugal (dibibit sebelumnya), dipindahkan ke tempat yang agak tinggi sebelum ditanam ke sawah rawa lebak.Begitu air rawa surut hingga tinggal 0,5-5 cm maka para perempuan banyak terlihat bertebaran di lahan menanam padi. Umumnya para perempuan bertugas menanam padi, sementara petani laki-laki hanya memikul bibit dari tempat pembibitan ke tempat perempuan menanam padi. Penggunaan mesin perontok padi bagi proses panen padi dilakukan oleh laki-laki. Hal ini karena mesin tersebut didesain untuk laki-laki, dan disosialisasikan kepada laki-laki melalui kelompok tani. Perempuan tidak diperhitungkan dalam penggunaan teknologi panen padi sehingga lagi-lagi peran perempuan terkurangi.Pengoperasi mesin grentek umumnya laki-laki meskipun ada juga perempuan yang bisa menggunakan alat ini. Ketergusuran kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga petani padi sawah lebak pada aspek ketersediaan padi mengakibatkan perempuan melakukan diversifikasi pekerjaan tani non padi. Perempuan bekerja sebagai pengumpul bahan pangan dari ekologi rawa. Kuasa pengetahuan perempuan tentang pangan yang bersumber dari ekologi rawa dipraktikkan untuk memilih jenis-jenis pangan yang bisa diolah menjadi makanan keluarga. Pada posisi demikian perempuan tetap bisa berperan dalam pemenuhan pangan keluarga. 54 Ekosistem rawa lebak memiliki keanekaragaman tumbuhan (flora) dan hewan (fauna) yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Tumbuhan yang hidup di lahan rawa lebak sangat beragam dari jenis pohon, perdu, semak, dan rumput.Macam, jenis dan keragamannya sangat tergantung pada kondisi lingkungan fisik (iklim, hidrologi, tanah, vegetasi, tipologi) serta pemanfaatannya.Jenis fauna yang hidup di rawa lebak sangat beragam dari golongan reptil, unggas, dan berbagai jenis ikan.Pengembangan perikananpada ekosistem rawa lebak ditopang oleh adanya vegetasi rawa. Pada umumnya didapati empat jenis vegetasi, yang dipakai sebagai pakan ikan yaitu 1) Vegetasi dibawah permukaan (emerged), 2) Tipe berdaun terapung (floating leaved) 3) Terapung bebas (free floating) 4) Tipe jenis rumput. Jenis ikan yang hidup pada ekosistem rawa tidak kurang dari 100 jenis, diantaranya ikan hitam; gabus, papuyu,sepat, biawan, patin, toman dan ikan putih, ikan yang umum berada di perairan sungai dan bisa ditemukan di rawa sebagai ikan pendatang. Selain ikan, hewan piaraan yang bisa terdapat di rawa adalah itik Alabio dan kerbau rawa (Noor, 2007). Perempuan memanfaatkan ekosistem rawa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut berasal dari sosialisasi dalam keluarga dan komunitas petani padi sawah lebak. Berbagai pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk menghadapi masalah pangan berdasarkan musim, yakni musim pasang (hujan) dan musim surut (kemarau). Pada musim pasang, para perempuan mencari ikan dengan cara memancing, menggunakan tangkul, dan jala.Hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk lauk makan keluarga petani padi sawah lebak.Jika mendapatkan tangkapan dalam jumlah banyak maka dijual kepada para tengkulak yang datang ke desa. Biasanya pada musim pasang, jumlahtangkapan ikan banyak berkonsekuensi pada murahnya harga ikan. Para perempuan tetap mencari ikan meskipun harga ikan mengalami penurunan untuk menambah tambahan pendapatan keluarga. Berikut penuturan para subyek kasus; “Kalu dapat ikan ninggali untuk makan, makan dulu baru dahnye dijual. Iwak itulah pendaping nasik tu. Neman makan ikan tulah, jarang ame makan buahbuahan tu. Ikan tu sepanang tau ade tulah, air pasang die ade, air surut ade disungai ni”. (Nursyam, Fatimah, Jasiyah) (Biasanya hasil tangkapan ikan untuk masak, kalau ada lebih baru dijual. Ikan menjadi menu tiap hari. Masyarakat disini lebih sering makan ikan daripada makan buah-buahan. Karena ikan disini ada sepanjang tahun, baik musim surut maupun pasang) Jenis-jenis ikan yang bisa mereka dapatkan adalah ikan seluang, betok, gabus, dan ikan putih lainnya yang berasal dari luapan sungai kedukan kijang yang mengitari desa Ulak Aurstanding. Bahkan beberapa perempuan sengaja menjadi pencari ikan sebagai pekerjaan utama saat musim pasang.Biasanya mereka membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang mencari ikan bersama.Setelah terkumpul mereka menjual menggunakan perahu sampan dari rumah ke rumah.Pada musim pasang perahu sampan menjadi alat transportasi di desa ini.Ada juga perempuan yang menjual ikan tangkapannya dengan berjalan kaki di sepanjang ruas jalan utama yang tidak tergenang air. Biasanya ikan dijual ketengandimasukkan dalam plastik kecil setiap plastik seharga Rp. 2.000,- dengan jumlah berat sekitar ¼ kilogram. Melimpahnya jumlah ikan saat musim pasang membuat hasil tangkapan melimpah sehingga muncul pekerjaan baru yakni buruh menyiang ikan.Para tengkulak ikan ada yang membeli ikan dalam bentuk ikan hidup, ada juga yang membeli ikan dalam bentuk sudah bersih (disiangi/diperut).Biasanya ikan yang sudah disiangi ini digunakan untuk membuat tekwan, model, empek-empek serta untuk krupuk kemplang. Upah menyerut/menyiang ikan ini sebesar Rp. 500,- perkillogram ikan bersih. Memang membutuhkan waktu lama, tetapi 55 para perempuan mengambil pekerjaan ini daripada menganggur di rumahnya.Ikan diantara ke salah satu rumah penduduk kemudian tetangga sekitar datang untuk menyerut ikan bersama-sama. Perempuan memanfaatkan keong rawa, masyarakat menyebutnya gondang, untuk dimasak sebagai lauk makan dan juga digunakan sebagai pakan itik peliharaan mereka. Gondang ini banyak ditemukan saat musim pasang.Perempuan membuka cangkang, menukil isi/dagingnya dan mengolahnya menjadi lauk atau sebagai pakan itik. Jika untuk lauk maka keong direbus terlebih dahulu sebelum diolah dengan bumbu sesuai selera, sedangkan untuk pakan itik, keong tersebut dicampur dengan dedak atau sisa makanan dan buah telepuk. Buah telepuk ini banyak hidup mengambang di permukaan air saat musim pasang. Selain untuk campuran makan itik, buah telepuk juga dmanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat desa Ulak Aurstanding. Para perempuan menggunakan sampan untuk mendapatkan buah telepuk dan keong rawa, sampai ke tengah rawa. Berikut gambar jenis bahan pangan keluarga petani padi sawah lebak yang diambil dari ekosistem rawa lebak: Gambar 8: Bahan pangan yang diperoleh dari ekosistem rawa; telur itik, keong/gondang dan buah telepuk Itik yang dipelihara masyarakat adalah itik jenis Alabio.Pengembangan itik ini dilakukan secara ekstensif dan intensif. Secara ektensif dilakukan dengan menggembalakannya ke luar kandang, ke lahan-lahan di sekitarnya. Pakan itik sangat tergantung pada keberadaan tanah rawa lebak yang secara alami menyediakan makanan seperti ikan-ikan kecil, cacing serta berbagai gulma air seperti eceng gondok, kangkung, kayu apu dan tumbuhan air lainnya. Sementara secara intensif dipelihara di dalam kandang. Setiap keluarga biasanya memiliki peliharaan bebek dan ayam dengan jumlah yang berbeda.Hewan peliharaan ini sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan keluarga karena mereka menjual telur ayam dan bebek jika memerlukan uang. Telur bebek dijual seharga Rp. 1.500,- perbutir. Mereka menjual ayam dan hewan piaraan tersebut di pasar kalangan.Pasar kalangan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli barang keperluan hidup sehari-hari. Pasar kalangan diadakan pada hari tertentu, satu kali dalam seminggu. Banyak pedagang dari luar desa, sengaja datang untuk menjual barang-barang yang tidak diproduksi masyarakat setempat. Para tengkulak juga datang untuk membeli barang seperti telur bebek, ayam kampung dan ikan. Pada musim air mulai surut, perempuan terlibat dalam proses pertanian padi sawah lebak. Dimulai dari pembuatan brondong (rumput panjang dianyam untuk media penyemaian bibit padi), menyingkirkan rumput yang tumbuh pada saat air pasang, menyemaikan bibit, memindahkan bibit, menanam padi dan memanen padi. Setelah panen padi perempuan menjemur padi sebelum padi simpan, atau digiling menjadi beras. Perempuan memanfaatkan lahan yang sudah surut lebih awal (lebak dangkal) untuk menanam berbagai jenis sayuran seperti kacang panjang, kangkung, cabai, tomat dan 56 labu. Tanaman biji-bijian yang sering ditanam yaitu jagung dan kacang tanah.Setiap jengkal tanah yang memungkinkan ditanami dimanfaatkan untuk tanaman tersebut. Pengetahuan perempuan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan tani non padi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut di atas, membuat perempuan mempunyai kuasa atas pangan keluarga. Sejalan dengan ini, Foucault mengungkapkan adanya hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan. Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait.Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan (Foucault 1980). 4.KESIMPULAN Resistensi kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga petani sawah lebak dilakukan sebagai akibat marjinalisasi peran perempuan dalam proses pertanian padi sawah lebak dan tekanan ekonomi keluarga. Bentuk-bentuk resistensi kuasa pengetahuan perempuan antara lain; resistensi langsung terhadap proses pertanian padi sawah lebak (penggunaan bibit lokal, membersihkan rumput secara manual dan penggunaan teknologi pertanian) dan resistensi tidak langsung dengan melakukan diversifikasi pekerjaan tani non padi, menenun songket, mengolah hasil perikanan rawa, membuat atap daun, membentuk organisasi non formal, mengakses kredit non formal, dan membuat konsumsi pangan keluarga. Pekerjaan tersebut menunjukkan adanya geliat ekonomi perempuan untuk pemenuhan pangan keluarga. Diversifikasi pekerjaan tani non padi menjadi ujung tombak kuasa pengetahuan perempuan dalam pemenuhan pangan keluarga. Ekologi rawa memberi peluang para perempuan mencari dan mengumpulkan bahan pangan, sehingga perempuan tetap berperan dalam ketersediaan pangan keluarga meskipun tergusur dari proses pertanian padi sawah lebak. 5.DAFTAR PUSTAKA Agger B. 2009. Teori Sosial Kritis. Terjemahan: Critical Social Theories: An Introduction. Yogyakarta (ID):Kreasi Wacana. Babatunde, O. Raphael.,& Qoim, Martin, 2010. Impact of off-farm income on food security and nutrition in Nigeria. Food Policy 35 (2010) 303-311. Elsevier Ltd Brennan. MA & Israel, G.D. 2008. The Power of Community. Journal of Community Development Society, Vol 39. No. 1. 2008. Carr R.Edward, 2006. Postmodern conceptualizations, modernist applications: Rethinking the role of society in food security. Food Policy 31 (2006) 14-29. Elsevier. www.sciendirect.com Chung K, Haddad J, Rama K, Riely F. 1997. Identifying The Food Insecure, The Application on Mixed Method Approacher in India, International Food Policy Research Institute, Washington DC. Denzin NK,Lincoln YS. 2009. Handbook of Qualitative Research. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta (ID):Pustaka Pelajar. Febriansyah A. 2014. Analisis kesejahteraan petani padi sawah lebak di kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir Palembang: Jurnal Ilmiah AgrIBA No 2 Edisi September tahun 2014. Foucault M. 1980. Power/knowledge, edited by Colin Gordon. New York (USA): Pantheon Books, Harvester Press. Gladwin H, Cristina, Thomson M, Anne. Peterso S, Jennifer & Anderson SA. 2001. Adressing food security in Africa via multiple livelihood strategies of women farmers. Food Policy 26 (2001) 177-207. Elsevier Ltd 57 Haddad L, Kasbur 1990. Intrahousehold Resource Allocation: Methods, Models, and Policy. John Hopkins University Mabsout R, Staveren V. 2010. Distentangling Bargaining Power from Individual and household Level to Institutions: Evidence on Women’s Position in Ethiopia. World Development, vol 38, No. 5, pp. 783-796. Elsevier Ltd McCullum C, Pelletier D. Barr D.& Wilkins J. 2003.Agenda Setting within a CommunityBased Food Security Planning Process: The Influence of Power. Research Brief. Society for Nutrition Education. McMichael, P. 2009.A food regime geneology. The Journal of Peasant Studies. Vol.36 No. 1, January 2009, 139-169. Maxwell S. Frankenberger TR. 1992. Household Food Security: concepts, indicators, measurement, A technical Review. Rome: International Fund for agriculture Development. United Nations Children’s Fund. Moussa C. 2011. Impact Assesment of Women Farmer Activity on Poverty Reduction and Food security: A case of Kindia Region/Guinea. Journal of Agriculture Science.Canadian Centre of Science and Education. Nanama S. & Frongillo A E. 2012. Women’s rank modifies the relationship between huosehold and women’s food insecurity in complex households in northern Burkina Faso. Food Policy 37 (2012) 217-225. Elsevier Ltd Rocheleau D.& Edmunds D. 1997.Women, Men and Trees:Gender, Power and Poverty inForest and Agrarian Landscapes.World Development, Vol 25, No 8, pp.13511371. Pergamon. Elsevier Science Ltd Scanlan J. Stephen. 2004. Women, Food Security, and Development inLess-Industrialized Societies: Contributions and Challenges for fhe New century. World Development Vol. 32, No 11, pp. 1807-1829. Elsevier Ltd Schiavoni C. 2009. The global struggle for food security: from nyeleni to New York. The Journal of Peasant Studies.Vol. 36 No. 3 July 2009, 682-689. Sen A. 1982. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivatio. Oxford (GB): Clarendon Press Sukiyono. 2008. Status Wanita dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan dan Petani Padi Di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Jurnal Agro Ekonomi Volume 26 no 2 Oktober 2008. Valdivia C, Gilles J. 2001. Gender and Resource management: household and groups, trategies and transitions. Agriculture and human Value vol 18, 5-9 Walingo M, Khakoni. 2009. Role of Livestock Projects in Empowering Women Smallholder Farmers for Sustainable Food Security in Rural Kenya. AJFAND Vol 9 No 7 Tahun 2009. 58 KEMISKINAN DAN AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN Ida Ruwaida Staf Pengajar Departemen Sosiologi Universitas Indonesia e-mail: [email protected] Abstrak Tulisan ini menfokuskan perhatian pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program penanggulangan kemiskinan dalam kaitannya dengan aksi kolektif perempuan. Berdasar kajian terefleksi bahwa kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan masih belum menstimuli kapasitas dan kesadaran kritis perempuan baik secara individual maupun kolektif. Artinya, perempuan masih diposisikan dengan peran instrumentalnya, bukan peran substantif/transformatifnya. Menariknya, ada kecenderungan programprogram yang ada justru menfragmentasi perempuan. Hal ini dimungkinkan ketika kebutuhan dan kesadaran perempuan untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan kepentingan bersama masih lemah. Pada sejumlah kasus, aksi kolektif perempuan sangat diwarnai oleh ada tidaknya figur sebagai “tokoh” yang memiliki kapasitas individual sebagai agen perubahan, yang mampu melakukannya apa yang disebut oleh Naila Kabier sebagai transformasi institusional, meski berhadapan dengan tantangan struktural dan kultural. Secara sosiologis, menarik mengungkap strategi agen perubahan dalam menyikapi tantangan-tantangan institusional yang ada. Abstarct This paper focuses attention on women's economic empowerment through poverty alleviation programs in relation to the collective action of women. Based on the study reflected that the policies and programs of poverty reduction is still not stimulate the capacity and critical awareness of women both individually and collectively. That is, women are still positioned with its instrumental role, not a substantive role / transformative. Interestingly, there is a tendency of existing programs instead menfragmentasi women. This is possible when the need and awareness of women to organize themselves and promote common interests, is still weak. In some cases, the collective action of women strongly colored by the presence or absence of the figure as a "leader" who has the individual capacity as an agent of change, is capable of doing what is called by Naila Kabier as institutional transformation, although faced with structural and cultural challenges. Sociologically, reveal interesting strategy change agents in addressing the institutional challenges that exist. Pendahuluan Pemerintah Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs), yang kini dikembangkan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), menempatkan kemiskinan sebagai salah satu masalah utama yang harus ditanggulangi. Data BPS, per September 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 28,51 juta jiwa (11,13 persen). Persentase penduduk miskin di desa jauh lebih besar (14,09 persen) dibandingkan kota (8.2%). Adapun gini ratio mencapai 0.41, yang mana kota lebih besar (0,43) dibanding 59 desa (0,33). Jika dilihat berbasis gender, maka data menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan secara ekonomi, lebih miskin. Berbagai faktor yang melatari tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai yang diberlakukan di masyarakat pada perempuan, yang kemudian mengkondisikan kelompok ini berpendidikan lebih rendah, nikah lebih muda, bergantung secara ekonomi pada laki-laki/keluarga, dll. Selama dua dekade terakhir, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan oleh pemerintah, yang pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan (antara 9 hingga 10 persen) dan juga menurunkan angka gini ratio atau ketimpangan pendapatan (target 0,39). Strategi yang dikembangkan bersifat terpadu baik menyasar pada rumahtangga maupun komunitas, bahkan pada perempuannya sendiri.3 Berkenaan dengan kondisi nyata bahwa kemiskinan lebih berwajah perempuan, berbagai program telah diluncurkan baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Salah satu yang terkini adalah program terpadu dan terintegrasi yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia adalah program “MAMPU” (maju perempuan Indonesia untuk penaggulangan kemiskinan), yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan (organisasi penggiat perempuan/gender). Menariknya, sebagian besar program, termasuk MAMPU (2012-2020), berpijak dari asumsi dasar bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Hasil kajian International Poverty Centre memang menunjukkan bahwa apabila perempuan tidak mengalami hambatan apapun dalam memasuki pasar tenaga kerja, maka kemiskinan akan berkurang setidaknya 25 persen di Argentina dan Brazil, sementara di Chili mencapai 40 persen. Sementara studi lain menegaskan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan SDM bagi anak perempuan, serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan (www.mampu.co.id). Berbasis dari berbagai kajian tersebut, pertanyaannya adalah apakah asumsi-asumsi diatas tercermin di Indonesia? Dengan kata lain, apakah program-program penanggulangan kemiskinan yang menyasar pada perempuan secara langsung maupun tidak langsung (misalnya: kelompok usaha bersama/KUBE, Simpan Pinjam Perempuan/SPP-PNPM, juga yang terkini MAMPU, serta program lainnya baik di level lokal/nasional/regional) akan memampukan atau memberdayakan perempuan baik secara ekonomi, sosial, bahkan politik.4 Artinya, seberapa besar kontribusi program seperti: pada peningkatan keberdayaan perempuan tidak hanya pada level individual, namun juga kolektif? Hal ini mengingat tantangan yang dihadapi perempuan bukan hanya pada komunitas/masyarakat, bahkan pada tataran rumahtangga. 3 Setidaknya 3 program penanggulan kemiskinan, yakni: program bantuan khusus pada rumahtangga sangat miskin ((RTSM) maupun miskin(RTM); pemberdayaan komunitas (PNPM, SPP, dll); dan penguatan ekonomi (KUBE, dll). Pada level rumahtangga, sejumlah program bantuan khusus antara lain: Bantuan Langsung Tunai (BLT atau BLSM); Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/KPS sebagai syarat mendapat BLSM, PKH, dll)); Kartu Indonesia Pintar (pemberian beasiswa semacam BSM, Bidik Misi, dll), Kartu 60 Indonesia Sehat (sebelumnya Jamkesmas), dan berbagai program sektoral. 4 Mayoux (2006) mengembangkan kerangka analisis yang menunjukkan bagimana program semacam micro-finance mempunyai dampak signifikan pada pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik. Bahkan lebih jauh dikatakannya bahwa akses terhadap tabungan dan pinjaman secara perlahan akan dapat mendorong atau memperkuat keterkaitan ketiga aspek pemberdayaan. Penanggulangan kemiskinan dan transformasi struktural Upaya mengatasi kemiskinan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender perlu diarahkan pada akar persoalannya yakni struktur, kondisi social, dan kultur masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Chafetz, perlu dilakukan penghapusan sistem normatif dan ideologis yang mendasari stratifikasi gender (jenis kelamin). Untuk itu perempuan selayaknya tidak berjarak dengan isu-isu kekuasaan dan politik sebagai arena strategis. Tujuannya untuk melakukan transformasi struktural penguasaan sumberdaya dari struktur ber-ketidakadilan ke struktur berkeadilan (Chafetz, 1988: 70-72; Lengermann dan Niebrugge, 2003: 410-411). Transformasi struktural, pada dasarnya, hanya dimungkinkan jika ada keberpihakan dan komitmen atas realitas yang dianggap tidak adil pada perempuan. Keberpihakan dan komitmen ini, menurut Seidman (1998:62), memungkinkan feminis bekerja sebagai pejuang perempuan yang melakukan aksi politik karena dilandasi pemahaman dan kesadaran bahwa perempuan mengalami ketimpangan karena adanya blok secara ideologis maupun sosial. Strategi pembebasan dari ketimpangan kekuasaan inilah yang kemudian dikenal sebagai pendekatan pemberdayaan. Menurut Kabeer (2005), pemberdayaan merupakan sebuah arena ‘kekuasaan’, yang membutuhkan kemampuan (the power within) dalam melakukan aksi nyata (power struggle) untuk mengakses, memanfaatkan, mengkontrol, dan bertanggungjawab atas sumberdaya demi perubahan yang diharapkan. Oleh sebab itu, melakukan upaya pemberdayaan tidaklah mudah karena berpilar pada pola relasi yang setara. Terlebih, idealnya pemberdayaan dilakukan pada empat level, yakni: individu, kelompok, organisasi dan komunitas. Dunst dkk (1990) juga menegaskan bahwa kinerja pemberdayaan juga dilihat dari kemampuan membangun jaringan sebagai sumber daya (Cannan and Warren, 1997:109-110). Dengan demikian, pemberdayaan sebagai aksi nyata bisa bergerak dari level individu ke kolektif, dari negosiasi privat ke aksi publik, dari ranah informal ke ranah formal. Sebab itu, proses dan parameter pemberdayaan menjadi isu signifikan bagi sebagian kalangan. Secara konseptual, jika Chafetz mengemukakan pemberdayaan merupakan transformasi struktural, maka Kabeer (2005) menawarkan transformasi institusional, yakni proses transformasi yang mensyaratkan adanya gerakan atau perjuangan di berbagai arena ‘kekuasaan’, yakni: dari individu ke kolektif, dari negosiasi privat ke aksi publik, dari ranah informal ke ranah formal. Berkenaan dengan strategi pemberdayaan dan dinamika power struggle di masyarakat, Mohanty (2005) menekankan perlunya keberadaan institusi yang fungsional dan krusial dalam proses demokrasi. Pertanyaannya: bagaimanakah merancang prosedur institusional yang berkontribusi positif pada substansi kekuasaan yang eksesif? Gagasan Kabeer (2005: 13-14) bisa diajukan sebagai alternatif jawaban, yakni pemberdayaan sebagai upaya transformasi insitusional perlu memperhatikan tiga aspek/dimensi yang saling terkait, yakni: agency, resources dan achievement. 61 Jika pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Mohanty (1995) merupakan upaya pemampuan masyarakat sipil, termasuk keberadaan organisasi masyarakat sipil yang representatif sebagai wadah partipasi, maka yang dipertanyakan adalah bagaimana membangun komitmen warga/anggota komunitas untuk melakukan tindakan kolektif secara terorganisir?. Artinya, dalam konteks melawan kemiskinan, bagaimana perempuan mengorganisir diri dan membangun aksi kolektif?. Agensi perempuan dan aksi kolektif Merujuk pada gagasan Kabeer tentang transformasi insitusional, maka persoalan pertama dan utama adalah menyangkut agensi. Pada dasarnya agensi merupakan konsep sentral pemberdayaan, yang merepresentasikan melalui mana power atau kemampuan melakukan pilihan dan mempertimbangkan konsekuensinya. Sedangkan sumberdaya adalah medium melalui mana agensi bekerja, adapun capaian adalah keluaran agensi. Konteks pemberdayaan sangat terkait dengan kerja agensi dalam kaitannya dengan struktur dan relasi kekuasaan. Ada dua alternatif yang dimungkinkan bagi agensi yakni ‘power to’ (bermakna positif, memilih berbeda) atau ‘power over’ (bermakna negatif, menguasai/cenderung koersif). Diakui Kabeer bahwa agensi berhadapan dengan norma ideologis dan kultural yang memungkinkan adanya bias. Implikasinya pilihan tindakan agensi bisa dalam bentuk: (1) agensi yang pasif (aksi dengan pilihan terbatas); (2) agensi yang aktif (bertujuan jelas); (3) agensi efektif (bertindak merujuk pada peran dan tanggungjawabnya); dan (4) agensi transformatif (mampu menantang batasan peran dan tanggungjawab). Merujuk pada konsepsi Dunst (1994), kemampuan perempuan sebagai agensi merupakan indikator kinerja (performance), sekaligus indikator proses pemberdayaan. Menurut Whitmore (1998), pemberdayaan sebagai proses merupakan aktivitas reflektif dari kelompok yang diberdayakan, untuk mampu menentukan nasib/kondisinya sendiri (self determination). Sementara, Young (1993:158) menegaskan bahwa perempuan menjadi terberdayakan melalui proses refleksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Paramaternya adalah membangun citra diri dan percaya diri yang positif, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, membangun kelompok yang kohesif, terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan aksi nyata. Dalam proses pemberdayaan, pihak-pihak yang berelasi perlu mengedepankan rasa saling menghargai, dan senantiasa melakukan refleksi kritis atas proses dan relasi yang terjalin. (Cohran dan Henderson, 1990 dalam Warren, 1997). Aksi kolektif merupakan bagian yang melekat dalam proses pemberdayaan. Secara konkrit, aksi kolektif perlu melalui tahapan: (1) membangun rasa ingin tahu/ketanggapan, (2) melakukan identifikasi atas berbagai kondisi perempuan, (3) berkembangnya kesadaran, bahkan rasa “marah” pada situasi dan kondisi yang dialami perempuan, (4) melakukan konsolidasi internal maupun ke pihak-pihak lain, (5) terbangun identitas kolektif, yang sekaligus mencerminkan kekuatan atau keberdayaan perempuan baik sebagai individu maupun kelompok kepentingan. Tahapan ini setidaknya merefleksikan bahwa kesadaran kolektif tidak bisa dipisahkan dengan berkembangnya kesadaran personal. Peran agensi tidak bisa dilepaskan dengan struktur sosial dan politik, termasuk interaksi antar aktor lokal. Untuk itu, Schneider dan Libercier (1995:12) menekankan pentingnya 62 upaya membangun rasa percaya diri diantara aktor yang beragam latar belakang, melalui: dialog dan sikap tanggap, juga membangun kesiapan/kemampuan untuk membagi kekuasaan dan mengkombinasikan sumberdaya/potensi lokal dengan prosedur dan sumberdaya administratif. Mengingat pemberdayaan merupakan reflextive activity dari kelompok yang powerless sehingga mampu memperjuangkan kepentingannya, maka kelompok/aktor lainnya diharapkan mampu berkolaborasi dalam menciptakan iklim (climate), relasi (relations), sumberdaya (resources), dan prosedur (procedure) yang bisa mengkondisikan terbangun rasa percaya diri kelompok yang marginal, rentan. Lebih dari itu, mereka juga mampu membagi kekuasaannya. Inilah yang oleh Himmelman (1994) disebut sebagai strategi pemberdayaan kolaboratif, yang bisa berbentuk: (1) mengorganisir masyarakat berdasar tujuan/kepentingan yang ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan, (2) menfasilitasi proses yang ‘menyatukan’ pihak -pihak luar dalam mendukung tujuan masyarakat yang difasilitasi (Sardjono, 2004: 172-173). Strategi kolaboratif menghantarkan pada pemahaman pentingnya sinergi atau koproduksi antar aktor dalam melakukan pemberdayaan sebagai upaya transformasi sosial. Sinergi ini -- meminjam gagasan pemikiran Durkheim -- hanya bisa dilakukan jika ada pembagian kerja yang bukan semata bertumpu pada fungsi ekonomi tetapi juga sebuah kekuatan moral. Adanya moral solidaritas ini sekaligus memperkukuh asumsi bahwa demokratisasi ekonomi terlekat dengan persoalan keadilan sosial, keadilan gender, bahkan keadilan diantara perempuan sendiri. Karenanya, bagi Durkheim upaya perubahan atau reformasi bersumber dari kekuatan masyarakat. Menurutnya, hal-hal ideal tidak bisa dibentuk dan ditetapkan lewat legislasi, tetapi harus dimunculkan oleh ‘tubuh’ yang paham, berkomitmen, dan mampu mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, ‘asosiasi perempuan’ signifikan dipersoalkan, termasuk keterikatan sosial didalamnya. Modal sosial perempuan dan aksi kolektif Dalam konteks keberdayaan perempuan secara kolektif inilah modal sosial perempuan menjadi elemen penting. Modal sosial yang dimaksudkan Putnam (1992) adalah seperangkat hubungan horisontal antar individu atau networks of civic engangement, yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jaringan ini terbangun dari interaksi antar perempuan, bahkan antar kelompok perempuan, dan mungkin antar kelompok perempuan dengan kelompok lainnya di komunitas, bahkan dengan kelompok ‘penindas perempuan’, sebagaimana yang distrategikan oleh feminis Sosialis. Dalam kaitan berelasi dengan ‘kelompok penindas’, Durkheim memang berbeda posisi dengan Karl Marx, karena Marx masih tetap melihat adanya perbedaan kepentingan mendasar antar kelompok dan sulit dicari titik temunya. Bagi Durkheim, meskipun ada perbedaan kepentingan, namun masih dimungkinkan dipertemukan melalui apa yang disebutnya sebagai ‘common morality’. Moralitas ini akan menjadi pendorong reformasi sosial (Durkheim,1938/1977 dalam Ritzer dan Goodman, 2004; Ritzer, 1996). Sementara Seidman (1998: 62) juga masih melihat peluang membangun ikatan sosial, bahkan mensyaratkan adanya spesialisasi dan interdependensi peran-peran sosial. Ikatan sosial inilah yang menjadi landasan terbangunnya kerjasama untuk pencapaian tujuan atau kepentingan bersama (Purdue, 1986:73-76). 63 Berkenaan dengan modal sosial perempuan, gagasan Durkheim juga menjadi bagian signifikan, khususnya tentang solidaritas sosial yang menjadi basis semangat kolektif (collective conscience) bahkan berkembangnya ‘collective representation’. Representasi kolektif mengkondisikan perempuan beragam latar belakang melebur menjadi “kelompok tunggal’ (single group) (Ritzer,1966). Representasi kolektif inilah yang menjadi agenda utama feminis. Meski diakui feminis gelombang ketiga menyadari adanya perbedaan di kalangan perempuan berdasar etnis, agama, status ekonomi, dan lainnya. Perempuan bukanlah kelompok yang homogen, karenanya membangun kesadaran kolektif, apalagi representasi kolektif bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, menurut Cornwal (2000), pembangunan yang partisipatif selayaknya mempertimbangkan diversitas perempuan dan implikasinya pada partisipasi maupun representasinya. Karenanya, Cornwal menegaskan pentingnya memberikan kerangka kembali kepada pembangunan partisipatif, khususnya terfokus pada 2 (dua) hal, yakni: kewarganegaraan (citizenship) dan hak berpartisipasi. Menurutnya, esensi partisipasi yakni memberikan suara dan pilihan, serta mengembangkan kapasitas manusia berikut organisasi dan manajemennya dalam memecahkan masalah guna memperbaiki kondisi atau situasi secara berkelanjutan. Konsekuensinya, partisipasi tidak dijabarkan berdasar derajat atau tingkatannya, melainkan pada bentuk/tipe partisipasi: nominal, instrumental, representatif dan transformatif. Realitas empiris program kemiskinan dan refleksi kritis Berlandaskan pemahaman bahwa pemberdayaan merupakan proses sekaligus kinerja, tentu menarik diungkap bagaimana wujudnya dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan membantu kelompok sasaran atau dampingan untuk mampu atau memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan dan mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupan mereka, dengan: (1) mengurangi dampak dari hambatan sosial atau pribadi dalam menerapkan kekuasaan, (2) meningkatkan kapasitas dan percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan (3) memindahkan kekuatan dari lingkungan kepada kelompok itu sendiri (Malcolm Payne, 1997: 266). Temuan menunjukkan bahwa tindakan kolektif perempuan umumnya masih lemah, yang ditandai dengan masih bertumpunya anggota pada figur penggerak. Selain itu, cenderung elitis/eksklusif. Kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya kohesi sosial diantara mereka, apalagi membangun kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak ekonomi secara kolektif. Padahal merujuk Young (1993:158), perempuan terberdayakan jika melalui refleksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Paramaternya adalah: membangun citra diri dan percaya diri yang positif, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, membangun kelompok yang kohesif, terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta melakukan aksi nyata. Dalam konteks ini, bisa dikatakan belum terbangun modal sosial perempuan, yakni seperangkat hubungan horisontal antar individu atau jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ditengah diversitas perempuan, sudah terjadi kontak fisik diantara mereka,bahkan terbangun perhatian dan kesadaran bersama. Namun, ikatan emosional bisa dikatakan masih lemah, khususnya antar anggota kelompok. Hal ini dilatari bukan semata adanya perbedaan latar belakang, namun lebih karena 64 subyektifitas anggota sudah terbatasi oleh persoalan ekonomi, sehingga relasi sosial yang terbangunpun lebih bersifat transaksional. Inilah yang mendasari tidak terbangunnya representasi simbolik. Meski kelompok bersifat sukarela, namun partisipasi perempuan didalamnya lebih bersifat nominal dan instrumental, bahkan fungsional. Apalagi seringkali ketua dianggap sebagai representasi simbolik organisasi, padahal ketua kelompok bisa jadi belum merepresentasikan kepentingan anggota. Menurut Putnam, hanya melalui interaksi-lah terbangun asosiasi horisontal (kelompok keanggotaan), yang merupakan sumber trust dan ikatan sosial sekaligus emosional. Asosiasi ini ditandai dengan pembiasan para anggota dan pengurus dalam bekerjasama, sehingga mampu mengembangkan solidaritas dan semangat publik (Robert Putnam, Robert Leonardi, Rafaella Nanetti, 1996, 36). Dalam kondisi demikian, upaya pengembangan/pemberdayaan ekonomi perempuan, tampaknya lebih berbasis perspektif komunitarian. Perspektif ini menfokuskan perhatian pada bentuk organisasi sosial yang potensial bagi perempuan dalam membangun komitmen antar perempuan. Padahal menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 425-429), hal terpokok dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal adalah pengembangan ekonomi alternatif berbasis masyarakat atau institusi ekonomi lokal, misalnya Lembaga Keuangan Mikro/LKM, Koperasi, Credit Union, dan lain -lain. Namun demikian, pengembangan dan penguatan institusi ekonomi lokal bukanlah hal yang mudah, salah satu tantangannya adalah pengorganisasian sosial di tingkat lokal, termasuk pelembagaannya (institusionalisasinya). Keberhasilan pengorganisasian sosial, tampaknya lebih berpilar pada isu yang nyata dan dasar di masyarakat yakni: ekonomi. Artinya, program yang ada menawarkan upaya pemenuhan kebutuhan praktis kepada masyarakat, termasuk perempuan. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar yang menentukan eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Karenanya, isu ekonomi (juga pendidikan, kesehatan) merupakan pintu masuk untuk menumbuhkan kepedulian perempuan dan masyarakat. Kedekatan isu pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat, akan menumbuhkan minat dan keinginan individu untuk kemudian berkelompok atas dasar kepentingan yang sama. Meski temuan menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih ‘mengelola usaha sendiri meski modal kecil’, namun isu ekonomi menjadi daya ikat. Daya ikat inilah yang mengarahkan perempuan berminat masuk kelompok dengan harapan mendapat bantuan ‘modal usaha’. Menurut Durkheim perlu ada pembagian kerja yang bukan semata fungsi ekonomi tetapi juga sebuah kekuatan moral. Menurutnya, hal-hal ideal tidak bisa dibentuk dan ditetapkan lewat legislasi/aturan, tetapi harus dimunculkan oleh ‘tubuh’ yang paham, berkomitmen, dan mampu mewujudkan hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, melalui ‘asosiasi’ diharapkan terbangun keterikatan sosial (Ritzer, 1996). Keterikatan sosial yang terbangun, bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik individu-individu di dalamnya. Kecenderungannya pembentukan kelompok lebih berbasis pada kekerabatan dan pertemanan, tanpa melakukan identifikasi yang cukup memadai tentang berbagai situasi dan kondisi yang dialami perempuan. Pada beberapa kasus, pembentukan kelompok berhasil dilalui dengan baik, dan sudah berjalan. Konsekuensinya, daya ikat atau keterikatan sosial antar anggota sudah terbangun, demikian pula aturan main dalam kelompok. Meskipun demikian, perbedaan latar belakang bahkan ‘kelas sosial’ menjadi tantangan tersendiri. Artinya, diversitas sosial pengelola dan 65 penerima program, bahkan kondisi keluarga dan masyarakat mewarnai dinamika komunitas sekaligus organisasi/asosiasi. Dalam konteks ini, adanya kontak bersama dan fokus/kepentingan bersama, sebagaimana disebutkan Collins, belum cukup menjamin terbangunnya asosiasi horisontal. Menurutnya, perlu ada kesamaan kondisi emosi diantara pihak-pihak yang ada, serta representasi simbolik bersama. Dua hal terakhir tidak mudah diwujudkan dalam komunitas dengan ciri: (1) ada ketimpangan sumberdaya diantar pelaku interaksi, (2) densitas sosial relatif tinggi, (3) derajat diversitas sosial cukup tinggi. Dalam upaya mengatasi ini, Barus berupaya menjembataninya dengan membangun kegiatan ‘pengajian rutin’ dua bulan sekali. Hal ini cukup berhasil, karena organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama merupakan hal sentral dalam masyarakat Sasak. Keaktifan masyarakat ini menunjukkan semangat kolektif (collective concience), dan sebaliknya semangat kolektif mencerminkan besaran ruang partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, tahap ‘pembentukan kelompok’ merupakan pondasi dalam membangun asosiasi horisontal (kelompok keanggotaan), mengingat asosiasi merupakan sumber trust dan ikatan sosial, melalui mana anggota membiasakan diri bekerjasama, mengembangkan solidaritas dan semangat publik (Putnam, Leonardi dan Nanetti, 1996:36). Dalam konteks aksi kolektif, tampaknya figur ketua juga menjadi inisiator sekaligus motor penggerak. Latarbelakang ketua ikut berpengaruh. Pertanyaannya, apakah figur ketua merepresentasikan kelompok/asosiasinya? Atau sebaliknya kelompok/asosiasi direpresentasikan melalui figur ketuanya? Berkenaan dengan ini, gagasan Durkheim menjadi bagian signifikan, apakah semangat kolektif (collective conscience) menjadi basis berkembangnya ‘collective representation’, yang mengkondisikan perempuan beragam latar belakang melebur menjadi “kelompok tunggal’ (single group) (Ritzer,1996). Representasi kolektif inilah yang menjadi agenda utama gerakan feminis/perempuan. Menurut Bambang Iswanto (2000), pada dasarnya kelangsungan dan kemandirian kelompok swadaya masyarakat (KSM), dapat dibangun melalui lima tahap, yakni: (1) penggalian motivasi dan proses penyadaran, (2) pembentukan organisasi, (3) tahap konsolidasi dan stabilisasi organisasi, (4) pengembangan usaha produksi dan pemasaran, serta (5) tahap kemandirian. Berkenaan dengan tahapan tersebut, jika merefleksikan pada sejumlah program keuangan mikro (KUBE, PEKKA, SPP-PNPM, dll) tampaknya keterbatasan proses rekrutmen anggota, ditemukan sejak tahap ke-1, karena motivasi anggota kelompok hanya pada bantuan modal usaha. Dalam kelompok pun tidak dilakukan upaya yang sistimatis dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan tanggungjawab, sekaligus kedisiplinan, serta kemandirian. Konsekuensinya derajat konsolidasi dan stabilisasi organisasi relatif rentan, kecuali ditopang oleh figur yang kuat. Merujuk pada tahapan yang dikemukakan Iswanto (2000), lemahnya tiga tahapan 66 di awal tentunya berkontribusi besar pada tahapan selanjutnya. Meski pada prinsipnya tidak berjalan linier, namun tahapan tersebut merupakan satu kesatuan. Contoh SPP (Simpan Pinjam Perempuan), terkesan kelompok tidak diorganisasikan secara kuat dan bahkan pembentukan kelompok lebih diorientasikan pada kemudahan mendapatkan dan atau memperbesar bantuan modal usaha. Karenanya, ketika logika program dimaknai bahwa besar kredit yang disalurkan merupakan indikator capaian proyek (kinerja pemberdayaan), sementara besaran kucuran kredit dipengaruhi oleh besaran kelompok, maka program lebih difokuskan pada upaya banyaknya kelompok yang dibentuk. Idealnya, proses awal pembentukan kelompok justru menjadi basis keberhasilan pengorganisasian sosial. Artinya, pengorganisasian sosial melalui kelompok, lebih terfokus dan termotivasi pada aspek ekonomi, khususnya pemberian dan pengembalian kredit. Dalam konteks ini pemampuan secara sosial kurang terefleksi, padahal pilar pembentukan kelompok merupakan dasar pemberdayaan secara sosial. Lemahnya pengorganisasian ini berbeda dengan praktek Grameen Bank, yang pembentukan kelompok dilakukan dengan kriteria ketat, yakni: beranggotakan 6 (enam) orang yang bukan kerabat dan seluruh anggota aktif dalam kegiatan. Keaktifan ini menjadi dasar penilaian atas kelayakan anggota mendapatkan bantuan. Melalui kelompok terbangun solidaritas dan aksi kolektif, yang juga menjadi prasyarat penerimaan bantuan kredit usaha. Dengan demikian ada aturan normatif yang menjadi acuan tindakan anggota, termasuk relasi antar anggota, dan diberlakukan relatif ketat. Berbeda dengan Indonesia, persyaratan dan mekanisme kurang memberdayakan perempuan sebagai individu maupun bagian dari kolektiva. Disinilah tanggungjawab sosial sekaligus moral selayaknya ditumbuhkan, meski relasi sosial dalam kelompok lebih bersifat fungsional (ekonomi). Refleksi dari Ikasari yang melakukan studi pada program PPSW di Jakarta memperlihatkan bahwa dalam kelompok, anggota melakukan pertemuan rutin, saling belajar, bahkan saling mengembangkan solidaritas (2003:70). Selain itu anggota dapat melakukan simpan pinjam, pengembangan usaha kelompok, juga memberikan bantuan dan memobilisasi sumber daya seperti dana sehat, beasiswa, jimpitan dan arisan. Dari pengalaman berorganisasi, anggota belajar bekerja sama-sama, menjadi pemimpin, dan mengambil keputusan dalam berbagai kegiatan sosial dan produktif yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Namun demikian, pada banyak kasus pengorganisasian sosial lebih bersifat terbatas dan partisipasi anggotanya masih cenderung nominal. Hal ini terkait dengan lemahnya solidaritas yang terbangun dalam kelompok, bahkan dengan pihak-pihak luar. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan latar historis pembentukan kelompok, termasuk tradisi berkelompok (sense of organized). Penutup Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan pemberdayaannya di bidang ekonomi, khususnya melalui pengembangan program usaha mikro dan atau bantuan kredit usaha (mikro), sejak tahun ’90-an tampaknya menjadi model yang mengglobal, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan perempuan. Pada konteks Indonesia, upaya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan pada dasarya sudah dilaksanakan beberapa dekade, melalui program pengembangan 67 usaha dan bantuan usaha/kredit mikro. Namun, realitas empirik di tingkat pemampuan perempuan secara ekonomi masih belum mencerminkan gagasan aksi Beijing yang telah digulirkan hampir 20 (dua puluh) tahun lalu. Keberdayaan secara sosial juga masih lemah, hal ini ditandai dengan bentuk partisipasi yang masih nominal, sedangkan agensi perempuan lebih berposisi sebagai agensi efektif belum sebagai agensi transformatif. Peran agensi lebih bersifat aktif, artinya meski mereka memiliki tujuan jelas namun belum mampu bekerja secara efektif (Kabeer 2005). Di sisi lain, negara (pemerintah lokal) masih belum cukup berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi perempuan baik secara substansial, institusional, bahkan kultural/normatif. Salah satu indikatornya adalah lemahnya refleksi atas berbagai program pemberdayaan yang sudah/tengah berjalan, sehingga terkesan sekedar melakukan replikasi (reproduksi) kebijakan/program, dengan menempatkan perempuan dan usaha mikro-kecil sebagai komoditas pembangunan. Imbasnya pembelajaran perempuan atas program pemberdayaan masih terbatas, meski program P4K sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Faktor lain yang membatasi perempuan adalah nilai-nilai gender, yang di kedua kasus relatif masih diberlakukan dengan ketat. Kondisi inilah yang melatari pilihan perempuan sebagai agensi pasif di sebagian wilayah, meski ada juga yang menempatkan diri sebagai agensi aktif, bahkan efektif, namun belum ditemukan yang tergolong transformatif. Kalaupun ada asosiasi perempuan di tingkat desa, tampaknya belum berperan sebagai ‘sekolah pemberdayaan’, karena proses ber’sekolah’ cenderung berjalan secara alamiah. Fasilitasi program tidak optimal dan tidak diorientasikan pada penguatan kelompok secara sosial, karena hanya menekankan pada dimensi ekonominya, bukan sosial dan politiknya. Terbatas atau miskinnya fasilitasi berimplikasi pada lemahnya kapasitas individual maupun kelompok yang diberdayakan. Sementara di sisi lain, determinasi pada figur penggerak menunjukkan lemahnya kinerja pemberdayaan, karena jejaring yang terbangunpun bertumpu pada figur/tokoh tersebut. Pada konteks fasilitasi inilah organisasi masyarakat sipil maupun organisasi basis selayaknya lebih berperan aktif, dan negara idealnya menfasilitasi dari aspek sumberdaya, termasuk kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan. Berbagai temuan yang ada menunjukkan pentingnya kejelasan upaya pemberdayaan baik sebagai proses maupun kinerja, termasuk indikatornya. Setiowati yang melakukan studi terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir di kabupaten Gunung Kidul menunjukkan belum optimalnya capaian tujuan program yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi msyarakat terhadap lingkungan (2006: 185- 187). Ketidakoptimalan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak dirancang secara partisipatif, bahkan sinergis. Hal ini mencerminkan lemahnya modal sosial antar warga/anggota, khususnya jika menyangkut akses dan kontrol atas sumberdaya ekonomi yang terbatas. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan replikasi program tidak diiringi upaya pembelajaran yang reflektif dari program-program sebelumnya. Pada dasarnya aksi reflektif merupakan salah satu prinsip pemberdayaan sebagai 68 proses sekaligus kinerja. Merujuk pada Dunst dkk, pemberdayaan sebagai kinerja tercermin dari kemampuan mengambil pesan pembelajaran melalui proses reflektif. Lemahnya modal sosial antar perempuan, juga menunjukkan keterbatasan pemberdayaan sebagai proses, yang didalamnya adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan misalnya membangun relasi, mentoring, aksi reflektif, dukungan kolektif, dan lain- lain. Sebagai proses, pemberdayaan merefleksikan pengalaman, sejarah, dan dinamika upaya pemampuan kelompok dampingan. Karena itu, pemberdayaan perlu waktu panjang (Cannan and Warren, 1997:109-110). Meski Konferensi Perempuan di Beijing, tahun 1995 sudah menegaskan perlunya: (1) merumuskan kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, khususnya perempuan, (2) revisi hukum dan kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan meningkatnya akses perempuan atas sumberdaya ekonomi, (3) meningkatkan akses perempuan atas perbankan, tabungan/investasi, mekanisme dan kelembagaan kredit, (4) mengembangkan riset dan monitoring atas sebab, dampak dan upaya mengatasi feminisasi kemiskinan (dapat dikaitkan dengan tindak lanjut atas ratifikasi konvensi hak ekonomi, sosial, budaya). Namun, kondisi nyata berbagai persoalan berkait dengan pemberdayaan perempuan, baik dari aspek kinerja maupun proses, masih berkutat dengan isu-isu tersebut. Keberadaan program MAMPU yang saat ini tengah masif dikelola di berbagai wilayah, keberhasilannya dalam memampukan perempuan secara ekonomi, sosial dan politik, masih dalam rumusan ‘hipotetis’. ---------------------------------Daftar Acuan Chafetz, Janet Saltzman. (1988). Feminist sociology: An Overview of Comtemporary Theories. Itasca-Illinois, F.E.Paecock Publishers.Inc. ----------------------------. (1989). Gender equality: Toward a theory of change. In Ruth Wallace (Ed). Feminism and Sociological Theory. (p.135-160). California: SAGE Publications, Inc. Hancock, Peter. (2001). Gender empowerment issues from West Java, in Susan Blackburn (Ed), Love, sex, and power: Women in southeast asia (h.75-88). Australia: Monash Asia Institute-Monash University Press Heyzer, Noeleen. (1994), Introduction: market, state and gender equity. In Heyzer, Noeleen and Gita Sen (ed). Gender, economic growth, and poverty: market growth and state planning in Asia and the Pacific. (p.3-27) The Netherlands: International Books in collaboration with Asian and Pacific Development Centre, Malaysia. Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2006), Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi, (Satatrawan Manulang, Nurul Yakin, & M.Nursyahid, penerjemah. 2008). Yogyakarta: Pustaka Pelajar 69 Kabeer, Naila. (1994). Reversed realitis : gender hierarchies in development thought. London-New York: Verso. Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge. (1996). Contemporary feminist theory. In George Ritzer, Sociological theory. (p.436-486). The McGraw-Hill Companies.Inc. Lengermann. Patricia Madoo, and Jill Niebrugge-Brantley. (2009). Teori feminis kontemporer. Dalam George Ritzer, Teori sosiologi. (hal.487-536). (Nurhadi, Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Parpart, Jane. (2002). Lessons from the field: rethinking empowerment, gender and development from a post-(post-?) development perspectives, in Feminist post-development thought: rethinking modernity, post-colonialism and representation. (p.41-56). Edited by Kriemild Saunders, London: Zed Books Ltd. Putnam, Robert, and Robert Leonardi, Rafaella Nanetti. (1992). “Making democracy work : Tradition in modern Italy”, Princenton, NJ: Princenton University Press. Pristiwati, Yuni dan Sri Harjanti Widyastuti. (2003). Merajut perubahan: Sebuah catatan harian perempuan dalam pengelolaan program pemberdayaan perempuan. Klaten: Persepsi. Pickering, W.S.F, (1998). Representation as understood by Durkheim: an introductory sketch, in WSF Pickering (ed). Durkheim and Representations: Routledge Studies in Social and Political Thought. (p.19-31). London and New York: Routledge. Seidman, Steven. (1998). Contested knowledge: social theory in the postmodern era, 2nd edtion, USA: Blackewell Publisher Inc. Warren, Chris et all. (1997). Social action with children and families: A community development approach to child and family welfare, London: Routledge. Young, Kate. (1993). Planning development with women: Making a world of difference, London and Basingstoke: The Maxmilllan Press Ltd. Cornwall, Andrea. (2000). Making a difference : Gender and participatory development”, IDS Discussion Paper 378. Institut of Development Studies, Isserles, Robin G. 2003, Microcredit: The rhetoric of empowerment, the reality of "development as usual", Women's Studies Quarterly, The Feminist Press at the City University of New York. Kabeer, Naila. (2005). Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third millenium development goals. Gender and Development Vol.13. No.3. Maret. 70 Mohanty, Manoranjan. (1995). On the concept of empowerment, Economic and Political Weekly, June 17. Ostrom, Elinor. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development, World Development, Vol. 24. No.6. Woolcock, Michael. (1998). Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework." Theory and Society 27 (2), page 151-208. Situs/Web Alejandro Portes and Patricia Landolt, “The Downside of Social Capital”, http://epn.org/prospect 26/26-cnt2.html. Miller C. and Razavi S (1998) Gender Analysis: Alternative Paradigms. UNDP Website http://www.undp.org/gender http://www.worldbank.org/participation/ participation.htm http://www.undp.org/gender/docs/mdgs-genderlens.pdf. 71 GERAKAN SOSIAL DUKUNG IBU MENYUSUI DI SUMATERA BARAT Novita Saseria Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Email:[email protected] Abstrak Penelitian ini mengenai gerakan sosial dukung ibu menyusui yang dikampanyekan oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Sumatera Barat. Hal ini menjadi perhatian dengan adanya temuan UNICEF terkait menurunnya tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia (Pekan ASI Dunia, Agustus 2013). Di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 10.457 bayi dari total 33.623 bayi yang belum mendapatkan kesempatan untuk menyusu secara eksklusif pada ibunya. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya dukungan untuk ibu menyusui dari lingkungan sekitar. Terhadap realitas tersebut penelitian ini mencoba menggunakan perspektif komunikasi untuk mengetahui bagaimana AIMI SUMBAR mengkampanyekan dukungan terhadap ibu menyusui di Sumatera Barat dengan melibatkan media massa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data pengumpulan dokumen, wawancara dan observasi terlibat. Hasil penelitian menunjukkan AIMI SUMBAR memanfaatkan media massa dalam mengkampanyekan pemberian ASI di Sumatera Barat dan bertambahnya pengetahuan masyarakat terkait pemberian ASI. Teori norma budaya menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan AIMI SUMBAR dengan melibatkan media massa yang ada mampu mengubah perilaku khalayaknya. Sehingga misi menjadikan menyusui dimanapun dan kapanpun menjadi norma di masyarakat Sumatera Barat. Kata Kunci: Gerakan Sosial, ASI, AIMI, Media Massa Abstract The research is about social movements on supporting breastfeeding mothers who campaigned by the Indonesia Breastfeeding Mothers Association (IBMA) Branch of West Sumatra. It is become important as the findings of UNICEF, who stated rates of exclusive breastfeeding in Indonesia decreased (World Breastfeeding Week, August 2013). In the West Sumatra Province, there are still 10,457 babies out of the total 33,623 babies who have not had the opportunity to breastfeed exclusively to their mother. One of the reasons is the lack of support for breastfeeding mothers from the surrounding environment. About the reality, the research tried to use communications perspective to discover how IBMA West Sumatra campaign of support for breastfeeding mothers in West Sumatra involving the mass media. This study uses qualitative method, with the techniques of data collection, interview and participant observation. The research showed that IBMA West Sumatra utilize the mass media in campaigning for breastfeeding and increasing public knowledge about breastfeeding. Cultural norms theory explains that the campaign conducted by IBMA West Sumatra involving the mass media is able to change the behavior of the audience. So that the aim to make breastfeeding wherever and whenever becoming the norm in the West Sumatra society can be reached. Keywords: Social Movements, Breastfeeding, IBMA, the Mass Media 72 1.PENDAHULUAN “It takes a village to raise a child, but to support breasfeeding we need the whole country” ~anonymous~ Air Susu Ibu (ASI) penting diberikan kepada bayi semenjak hari pertama kehidupannya hingga berusia 2 tahun atau lebih. Pentingnya pemberian ASI karena banyaknya manfaat ASI bagi bayi dan ibu, bagi bayi manfaat ASI sebagai perlindungan optimal terhadap berbagai penyakit infeksi. Manfaat ASI terlihat hingga puluhan tahun. Penelitian menunjukkan orang dewasa muda yang saat bayi disusui memiliki resiko lebih rendah terhadap berbagai penyakit kronis. ASI dapat meningkatkan kecerdasan anak. ASI juga dapat meningkatkan perkembangan emosi, kepribadian dan percaya diri. Sedangkan bagi ibu, manfaat menyusui dapat mencegah pendarahan setalah persalinan dan resiko anemia, menunda kesuburan (KB alami), mengecilkan rahim, mengurangi kemungkinan osteoporosis, rematik, diabetes mellitus, dan resiko kanker. Selain itu bagi keluarga ASI bermanfaat membantu perekonomian karena mengurangi biaya pembelian susu dan menghemat biaya pengobatan karena anak jarang sakit. Anak-anak yang mendapat ASI eksklusif 14 kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam bulan pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. Mulai menyusui pada hari pertama setelah lahir dapat mengurangi risiko kematian baru lahir hingga 45 persen.2 Menurut Deputi Direktur Eksekutif UNICEF Geeta Rao Gupta “Tidak ada intervensi kesehatan tunggal lainnya yang memiliki dampak setinggi ini untuk bayi dan ibu menyusui, dan dengan biaya yang sangat kecil bagi pemerintah, ASI adalah 'imunisasi pertama' bayi dan penyelamat hidup yang paling efektif dan murah.” Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Millenium atau lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tekad untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dijelaskan dalam Tujuan ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak. Anak-anak, terutama bayi, lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi hidup yang tidak sehat. Tingginya angka kematian bayi dan masalah gizi pada bayi dapat ditangani sejak awal dengan cara pemberian ASI. Menurut penelitian yang dilakukan oleh United Nation Children Fund (UNICEF), risiko kematian bayi bisa berkurang sebanyak 22% dengan pemberian ASI Ekslusif dan menyusui sampai 2 tahun. Khusus untuk kematian neonatus dapat ditekan hingga 55% - 87% jika setiap bayi lahir dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan diberikan ASI Eksklusif. Selain itu kasus kurang gizi pada anak di bawah usia dua tahun juga dapat diatasi melalui pemberian ASI Eksklusif. Semua bayi perlu mendapat ASI untuk mengatasi masalah gizi dan mencegah penyakit infeksi. 3 Selanjutnya, hasil penelitian John D. Benson, Ph.D., dan Mark L. Masor, Ph.D., dalam jurnal medik Endocrine Regulations terbitan Maret 1994 menyebutkan bahwa ASI mengandung sel-sel hidup, DNA ibu, hormon, enzim-enzim aktif, berbagai macam immunoglobulin, faktor-faktor pertumbuhan serta zat-zat lainnya yang memiliki komponen struktur yang unik. Zat-zat inilah yang sangat dibutuhkan bayi di hari-hari pertama kelahirannya. Komponen struktur yang unik tersebut mustahil untuk dapat ditiru oleh formula. Pernyataan dua peneliti ini cukup menarik perhatian karena John dan Mark adalah peneliti pada perusahaan produsen susu formula Abbot Labs. Douglas College Breastfeeding Course for Health Care Providers sebagai salah satu program penelitian ilmiah yang fokus terhadap ilmu laktasi telah menghasilkan 2 http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21270.html Yulien Adam dkk, determinan pemberian asi ekslusif di wilayah puskesmas Telaga biru dan puskesmas mongolato Kabupaten gorontalo provinsi gorontalo Tahun 2012, Jurnal Unhas. http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d0816d1d5f891249ac679ff93b0741ba.pdf 3 73 berbagai penelitian seperti teori laktasi, informasi konseling laktasi dan observasi kegiatan menyusui. Salah satu hasil penelitian breastfeeding course ini yaitu perbandingan kandungan nutrisi ASI dengan kandungan nutrisi susu formula. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel. Sumber : http://themilkmeg.com/ingredients-in-breastmilk-versus-artificial-breastmilkformula/ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan ASI yang dapat memenuhi kebutuhan bayi mulai dari air, protein, non protein, lemak, vitamin, mineral, zat-zat untuk pertumbuhan, enzim baik dan anti bakteri empat sampai lima kali lipat lebih banyak dari kandungan yang terdapat dalam susu formula. Bahkan, penelitian lain menyebutkan kandungan di dalam ASI masih mungkin bertambah dari data diatas. Hanya saja, informasi kandungan ASI ini belum dapat menyentuh masyarakat seperti informasi kandungan susu formula yang lebih mudah diakses di berbagai media dan tempat. Jika saja, peraturan pemasaran susu formula dapat diatur oleh pemerintah sehingga akses informasi ini berimbang, kampanye pemberian ASI dapat lebih mudah dilakukan. Dengan banyaknya manfaat ASI, dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, UNICEF dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui ASI selama paling sedikit 6 bulan. Makanan padat seharusnya diberikan sesudah anak berumur 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun 4. Melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dapat 4 Pusat Data informasi Kementrian Kesehatan RI, Situasi dan Analisis ASI Eksklusif. 2014 74 menjamin kecukupan gizi bayi serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh pemerintah republik Indonesia yakni pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengubah rekomendasi lamanya pemberian ASI eksklusif dari 4 bulan menjadi 6 bulan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 450/menkes/SK/IV/2004 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia. Pusat media UNICEF Indonesia menyatakan tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia menurun (Pekan ASI dunia, Agustus 2013). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dari 2.483.485 bayi usia 0-6 bulan, sebanyak 1.348.532 bayi atau sekitar 54,3% dari total bayi. Maka, sebanyak 1.134. 953 bayi tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan asi eksklusif. Kenyataan rendahnya pemberian ASI Eksklusif oleh ibu menyusui di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu, pertama, faktor internal meliputi rendahnya pengetahuan serta sikap ibu tentang kesehatan secara umum dan ASI eksklusif secara khusus. Kedua, faktor eksternal, yang meliputi kurangnya dukungan keluarga, masyarakat, petugas kesehatan maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan terhadap pemberian ASI eksklusif, gencarnya promosi susu formula, adanya faktor sosial budaya serta kurangnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menyadari bahwa pencapaian tujuan dan target MDGs bukanlah semata-mata tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa, sekumpulan ibu-ibu yang paham akan hal ini membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). AIMI merupakan wujud gerakan sosial dukung ibu menyusui di Indonesia. Gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu (Turner & Killian, 1972). Sedangkan menurut Giddens (1993), gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Dari dua pengertian menurut para ahli diatas maka AIMI yang memiliki 15 cabang yang tersebar di Indonesia bergerak secara kolektif untuk mendorong tercapainya target Tujuan Pembangunan Millenium sebagai salah satu komponen bangsa diluar pemerintah. Dalam gerakannya, AIMI fokus dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ASI. AIMI sebagai organisasi nirlaba non-pemerintah yang tidak memiliki dana dan anggaran tetap dalam mencapai tujuannya memiliki tantangan yang cukup sulit. Selain dana yang terbatas dan bersifat swadaya, gerakan ini bersaing dengan sebaran informasi dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak pro-ASI, gencarnya promosi susu formula dan minimnya perlindungan hukum terhadap hak ibu dan bayi mendapatkan ASI. Dari tahun ke tahun, gerakan ini semakin mendapatkan ruangnya, mulai dari berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi dan publikasi, membentuk cabang di berbagai daerah di Indonesia sampai dengan bergabung bersama LSM dan NGO nasional dan internasional membentuk Koalisi Advokasi ASI Indonesia yang menerbitkan regulasi di bidang menyusui. Cabang-cabang AIMI se-Indonesia telah menginspirasi sekumpulan wanita di Sumatera Barat untuk membentuk cabang AIMI Sumatera Barat, karena tidak jauh berbeda dengan permasalahan di berbagai daerah, cakupan pemberian ASI di provinsi Sumatera Barat belum mencapai target. Masih terdapat 10.457 bayi dari total 33.623 bayi (menurut data riskesdas) yang belum mendapatkan kesempatan untuk menyusu secara eksklusif pada ibunya di Provinsi Sumatera Barat. Pada 14 Juni 2015, AIMI Cabang Sumatera Barat (AIMI SUMBAR) diresmikan di Padang. Dalam gerakannya AIMI SUMBAR juga memiliki kendala yang kurang lebih 75 sama yaitu dana swadaya dan menghadapi sebaran misinformasi terkait ASI. Mitos yang berkembang dan dukungan yang minim di masyarakat menjadi tantangan. Terhadap realitas tersebut penelitian ini mencoba menggunakan perspektif komunikasi untuk mengetahui bagaimana AIMI SUMBAR mengkampanyekan dukungan terhadap ibu menyusui di Sumatera Barat? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana gerakan AIMI SUMBAR dalam mengkampanyekan dukungan terhadap ibu menyusui di Sumatera Barat. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana organisasi nirlaba bergerak mendorong perubahan dalam masyarakat dan dapat mendorong organisasi nirlaba lainnya melakukan hal serupa. 2.TINJAUAN PUSTAKA Gerakan Sosial dan AIMI Gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu (Turner & Killian, 1972). Sedangkan menurut Giddens (1993), gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Gerakan wanita sebagai salah satu bentuk gerakan sosial hendaknya mampu mendorong perubahan dalam masyarakat. Gerakan wanita di Indonesia tercatat menjelang akhir abad ke-19. Tokoh wanita pada jaman itu adalah Kartini. Kartini pernah menulis: “Siapakah yang akan menyangkal bahwa wanita memegang peranan penting dalam hal pendidikan moral dalam masyarakat. Dialah orang yang sangat tepat pada tempatnya. Ia dapat menyumbang banyak (atau boleh diatakan terbanyak) untuk meninggikan taraf moral masyarakat. Alam sendirilah yang memberikan tugas itu padanya. Sebagai seorang ibu, wanita merupakan pengajar dan pendidik yang pertama. Dalam pangkuannya lah seorang anak pertama-tama belajar, merasa, berpikir dan berbicara, dan dalam banyak hal pendidikan pertama ini mempunyai arti yang besar bagi seluruh kehidupan anak” “Tangan ibulah yang dapat meletakkan dalam hati sanubari manusia unsur pertama kebaikan atau kejahatan, yang nantinya akan sangat berarti dan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Tidak begitu saja dikatakan bahwa kabaikan ataupun kejahatan itu diminum bersama susu ibu” Perkumpulan wanita ketika itu sangat erat hubungannya dengan pergerakan kebangsaan Indonesia di berbagai bidang dengan tujuan khusus yaitu memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita. Perkumpulan tersebut bergerak terutama di bidang pendidikan, disamping keterampilan lainnya seperti memasak dan menjahit. Selain itu ada juga perkumpulan yang bersifat keagamaan. Menjelang tahun 1928 perkumpulan wanita berkembang semakin pesat. Ruang lingkup dan cara perjuangan perkumpulanperkumpulan tersebut beraneka ragam. Ada yang menganut paham nasionalisme, ada yang berhaluan politik dan ada yang tidak mencampuri urusan politik sama sekali 5. Bentuknya pun beraneka ragam mulai dari perkumpulan keluarga saja, yang sekarang dikenal dengan perkumpulan arisan, sampai dengan yang memiliki tujuan yang konkret, inilah yang sekarang dikenal dengan organisasi wanita. Perkumpulan wanita pada awal abad ke-20 ini mulai tersebar di Pulau Jawa, Jakarta, Semarang, Madiun, Malang, Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, Rembang, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Ciamis, Cicurug, Kuningan, Sukabumi, Magelang, Pemalang, Tegal, Jogjakarta, Garut. Kemudian semakin berkembang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. 5 GA Ohorella dkk, Peranan wanita Indonesia dalam masa pergerakan nasional, 1992, Direktorat Jenderal Kebudayaan 76 Di Sumatera Barat, pada tahun 1914, berdiri perkumpulan “Kerajinan Amai Setia” di Koto Gadang. Dengan tujuan meningkatkan derajat kaum wanita dengan mengajarkan baca-tulis huruf Arab dan Latin, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan, bahkan mengatur pemasarannya. Kerajinan Amai Setia mendirikan sekolah yang merupakan sekolah pertama untuk anak perempuan di Sumatera. Sekolah yang diprakarsai Kerajinan Amai Setia ini mempengaruhi gerakan wanita di Sumatera Barat. Pada tahun 1922 Dinniyah Putri School didirikan. Sampai dengan saat ini, Dinniyah Putri School masih menjadi salah satu tempat pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berprestasi di berbagai bidang. Saat ini perkumpulan atau organisasi wanita sudah tidak dapat dihitung lagi jumlahnya. Perkumpulan wanita semakin berani, tegas dan terbuka. Mengikuti perkembangan teknologi dan bergerak semakin luas. Perkumpulan ini memiliki misi masing-masing dan bergerak secara kolektif. Gerakan ini sudah makin terorganisir dan bahkan telah banyak yang berbentuk organisasi yang berbadan hukum. Gerakan sosial dimana orang-orang yang berkumpul didalamnya saling terkait lebih mungkin terorganisir daripada persatuan yang dibentuk. Organisasi gerakan sosial adalah sebuah organisasi yang kompleks atau formal yang mengidentifikasi tujuannya beserta pilihannya dalam sebuah gerakan sosial atau berlawanan dengan sebuah gerakan dan mencoba untuk mengimplementasikan tujuan-tujuannya (Mc Carthy, 2015). AIMI merupakan sebuah organisasi dalam sebuah gerakan sosial dukung ibu menyusui di Indonesia. AIMI terbentuk pada tanggal 21 April 2007 di Jakarta. Berawal dari kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi. Komunitas ini dilatarbelakangi karena melihat dukungan untuk ibu yang memberikan ASI kepada bayinya dirasakan kurang, baik perhatian dan dukungan dari pemerintah, masyarakat umum dan instansi swasta. Selain itu upaya sosialisasi mengenai pentingnya ASI bagi kesehatan dan imunitas bayi serta penyebaran informasi mengenai ASI dinilai masih sangat kurang. Kondisi ini diperparah pula dengan belum adanya dukungan kepada keluarga Indonesia, terutama ibu-ibu untuk mendapatkan akses informasi selengkap mungkin mengenai ASI baik dari rumah sakit tempat melahirkan dan tenaga kesehatan. AIMI memiliki visi, pertama, menaikkan persentase angka ibu-ibu menyusui di Indonesia. Kedua, menaikkan prosentase bayi yang diberikan ASI eksklusif di Indonesia. Ketiga, agar setiap ibu di Indonesia memiliki bekal pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai pentingnya pemberian ASI kepada bayi mereka. Keempat, agar setiap ibu di Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun atau lebih. Kelima, agar Pemerintah, perusahaan-perusahaan dan pihak ketiga lainnya sadar akan pentingnya ASI dengan mendukung penuh pemberian ASI kepada bayi-bayi di Indonesia. Keenam, agar masyarakat luas mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang ASI, dan memberikan dukungan dalam rangka mensukseskan pemberian ASI bagi bayi-bayi Indonesia. Sedangkan visi AIMI, pertama, memberikan informasi, pengetahuan dan dukungan bagi para ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun atau lebih. Kedua, memberikan masukan untuk pemerintahan, perusahaan dan instansi swasta agar mereka mengetahui pentingnya pemberian ASI, dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut dapat memberikan dukungan bagi suksesnya pemberian ASI. Ketiga, memberikan pendidikan kepada lingkungan masyarakat akan pentingnya ASI dengan terus-menerus memberikan pengetahuan dan informasi 77 terkini mengenai ASI. Keempat, mensosialisasikan risiko pemberian susu formula kepada bayi yang berusia kurang dari 2 tahun.6 Berawal dari dua ruang maya, www.asyforbaby.blogspot.com dan milis asyforbaby (sekarang [email protected]). Pada tahun 2006, milis merupakan salah satu media komunikasi yang cukup punya pengaruh penting. Media ini dipilih karena para penggunanya merasakan kenyamanan bersosialisasi untuk berbagi hal yang sama. Berbagi informasi dan dukungan positif dari lingkungan sekitar agar seorang bayi bisa mendapatkan haknya yaitu ASI dan sang ibu bisamendapatkan kesempatan menyusui dimanapun dan kapanpun. 7 Blog menjadi sebuah forum komunikasi bagi siapapun yang membutuhkan dan anggota milis terus bertambah. Pertumbuhan tersebut mendorong anggota milis untuk saling bertatap muka. Pertemuan ini melahirkan banyak ide dan wacana. Akhirnya pada tanggal 21 April 2007, bertempat di Jakarta Selatan, sebuah pertemuan menghasilkan deklarasi berdirinya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. AIMI semakin memiliki eksistensi dengan hadir di beberapa kegiatan baik nasional maupun internasional dari tahun 2007 sampai dengan 2016 antara lain kegiatan di istana negara bersama Duta ASI ibu Ani Yuhoyono, training dan seminar bersama NGO internasional (IBFAN, UNICEF dll), mengikuti One Asia Breastfeeding Partners Forum, advokasi dengan pemerintah dan terlibat dalam penyusunan peraturan terkait ASI, turun ke daerah bencana, dan kegiatan lainnya. Sampai dengan tahun 2016, AIMI telah memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia dan menerbitkan beberapa buku yang ditulis oleh pengurusnya. Air Susu Ibu (ASI) ASI menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Pasal 1 ayat 1 adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Menurut Wikipedia ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. ASI pertama yang keluar disebut kolostrum yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit. Berbagai kajian dalam dua dekade terakhir makin mmperlihatkan bahwa ASI adalah nutrisi terlengkap dan terbaik.Nilai nutrisi ASI lebih besar dibandingkan susu formula, karena mengandung lemak, karbohidrat, protein dan air dalam jumlah yang tepat untuk pencernaan, perkembangan otak dan pertumbuhan bayi. Kandungan nutrisinya yang unik menyebabkan ASI memiliki keunggulan yang tidak dapat ditiru oleh susu formula manapun. Susu sapi mengandung jenis protein yang berbeda yang mungkin baik untuk anak sapi, tetapi bayi manusia sulit mencernanya. Bayi yang mendapat susu formula mungkin saja lebih gemuk dibanding bayi yang mendapat ASI, tetapi belum tentu lebih sehat8. 24 jam setelah ibu melahirkan adalah saat yang penting untuk keberhasilan menyusui selanjutnya. Bayi dianjurkan disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI, idealnya selama 2 tahun pertama kehidupan. Kolostrum yang keluar beberapa jam pertama kehidupan berfungsi melapisi saluran cerna agar kuman tidak dapat masuk ke dalam aliran 6 http://aimi-asi.org/about/ Adenita, Breastfriends Inspirasi 22, 2013, Buah Hati. Tangerang, hal 25 7 8 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Indonesia Menyusui, Badan Penerbit IDAI, 2010, hal 1 78 darah dan akan melindungi bayi sampai sistem imunnya (sistem kekebalan tubuh) berfungsi dengan baik. Banyak penelitian yang menilai pengaruh jangka pendek dan panjang dari menyusui terhadap kesehatan bayi dan anak. Menyusu eksklusif selama 6 bulan terbukti memberikan risiko yang lebih kecil terhadap berbagai penyakit infeksi. Menyusu dapat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual anak. Anak yang disusui mempunyai intelegensia dan emosi yang lebih matang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya di masyarakat. Menyusui juga memberi keuntungan untuk ibu karena praktis dan meningkatkan kadar antibodi dalam darah sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi setelah melahirkan, mengurangi pendarahan post partum, mengurangi resiko kanker payudara, kanker ovarium dan osteoporosis. Tidak hanya bagi ibu dan bayi, menyusui juga memberikan keuntungan bagi keluarga, sistem pelayanan kesehatan, pemberi kerja dan negara secara keseluruhan. Keluarga dapat karena tidak perlu membeli susu formula. Bayi jarang sakit, sehingga lebih jarang berobat ke dokter dan rawat inap sehingga dapat menurunkan anggaran negara. Menyusui memiliki cukup banyak tantangan, misalnya dukungan dari lingkungan sekitar dan tempat bekerja. Ibu menyusui yang bekerja membutuhkan lingkungan yang bersih, suasana yang nyaman, jadwal kerja yang fleksibel. Idealnya, fasilitas perawatan bayi disediakan di tempat kerja. Apabila tempat bekerja tidak memiliki program menyusui, ibu harus meminta kepada atasannya untuk merancang kebutuhan tersebut. Hal ini telah diatur oleh Perauran Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Asi Eksklusif pasal 30 ayat 3 yaitu pengurus tempat kerja dan penyelenggaran tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Selanjutnya dalam Pasal 34 pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan asi eksklusif kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja. Secara keseluruhan proses menyusui melibatkan 4 faktor yaitu, bayi, payudara, ASI dan otak ibu. Kita seringkali meremehkan peran otak ibu dalam proses menyusui (Badriul Hegar, 2010). Perasaan depresi, marah dan nyeri harus dihindarkan saat menyusui karena dapat menghambat produksi ASI. Karena itu dukungan dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi keberhasilan menyusui. Menyusui sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Para ahli sejarah menemukan bukti-buki tentang menyusui. Di Peru, ditemukan sebuah artefak keramik tanah liat berbentuk ibu menyusui yang berasal dari kebudayaan Monche (1-800SM). Di India karya Brahmana menuliskan para wanita india menyusui sejak abad ke-2 menyusui anakanaknya. Di agama Hindu, Dewi Parvati, digambarkan sedang menyusui putranya dewa pengetahuan dan kecerdasan, Ganesha. (Adenita, inspirasi 22) Media Massa dan Teori Norma dan Budaya Media massa adalah alat yang digunakan untuk mengirim pesan ke khalayak besar. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya (MC.Quail.2005:3). Media massa membantu memperbanyak, menduplikasi atau memperkuat pesan untuk disebarkan ke khalayak yang lebih besar9. Fungsi dari media massa adalah (Mc.Quail. 1994:70):10 1. Informasi, menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia Menunjukkan, hubungan kekuasaan, Memudahkan inovasi adaptasi dan kemajuan. 9 Brent D Ruben, dkk, Komunikasi dan Perilaku Manusia, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal 209 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-media-massa-definisi-fungsi.html 10 79 2. Korelasi, menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, melakukan sosialisasi, mengkoordinasikan ngbeberapa kegiatan, membentuk kesepakatan dan menentukan urutan prioritas. 3. Kesinambungan, mengekspresikan budaya dominant dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru, meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 4. Hiburan, menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi, meredakan ketegangan sosial. 5. Mobilisasi, mengkampenyakan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan, ekonomi, pekerjaan dan agama. Media massa dapat dibagi menjadi 3 kelompok : 1. Media Massa Cetak Media massa yang dicetak dalam lembaran kertas. 2. Media Massa Elektronik Media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro. 3. Media Online (Online Media, Cybermedia), yakni media massa yang dapat kita temukan di internet (situs web). Media cetak adalah suatu media statis yang mengutamakan fungsinya sebagai media penyampaian informasi. Maka media cetak terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau dalam tata warna dan halaman putih, dengan fungsi utama untuk memberikan informasi atau menghibur. Media cetak juga adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya (Ardianto & Lukiati , 2004: 99). Media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buku dan bulletin. Media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis), media elektronik kini terdiri dari (Muda, 2005: 4) radio, film dan televisi. Media online muncul dikenal juga sebagai media baru. Media baru muncul di hampir semua aspek kegiatan sosial dan professional kontemporer. Fenomena tersebut terbukti saat ini pengguna internet bertambah dari tahun ke tahun. Membentuk teori-teori baru dalam komunikasi massa dan media. Penelitian-penelitian satu dekade terakhir dikembangkan dalam memahami sistem media baru. Pengguna internet di Indonesia pun mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dampak media baru telah dan akan berhasil membentuk gerakan sosial yang baru. Gerakan sosial pada umumnya memiliki empat elemen yaitu jaringan organisasi, identitas kolektif bersama, memobilisasi masyarakat untuk bergabung dengan cara yang tidak konvesional dan dalam rangka mencapai suatu tujuan sosial (Peter:2005). Elemen-elemen telah dimiliki AIMI sebagai oragnisasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan berafiliasi dengan organisasi internasional mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung ibu menyusui agar tercapai target MDGs. Teori Norma Budaya atau The Cultural Norms Theory dari Melvin L DeFleur menjelaskan bahwa media massa secara selektif menyajikan dan menekankan ide-ide, nilai-nilai atau norma-norma dengan memperkuat atau mengubahnya11. Teori ini memiliki hakikat bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema tertentu, menciptakan kesan pada khalayak di mana norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu, dibentuk dengan cara tertentu. 11 https://ethicsinpr.wikispaces.com/Cultural+norms 80 Norma adalah suatu patokan dalam berperilaku yang memungkinkan seseorang menentukan apakah tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain yang juga merupakan ciri bagi orang lain untuk menolak atau mendukung dari perilakunya (Robert M. Z. Lawang)12. Norma dapat berupa aturan yang mengatur perilaku dalam situasi tertentu di masyarakat. Menurut teori norma budaya media komunikasi dapat menciptakan keyakinan baru mengenai hal -hal di mana khalayak sedikit banyak telah memiliki pengalaman sebelumnya. 3.METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Menurut Afrizal (2014), kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan demikian tidak menganalisis angka-angka. Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen, wawancara dan observasi terlibat. Observasi partisipan yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti.13. Peneliti menjadi bagian dan diterima menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang diteliti. Peneliti melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka. Analisis data mulai dilakukan dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan, yaitu analisis berkelanjutan (ongoing analysyis).14 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN Menurunnya tingkat pemberian ASI Eksklusif di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi harus disadari sebagai tanggung jawab bersama seluruh lini dan lapisan masyarakat. Menyadari setiap orang dapat mendukung dan dukungan setiap orang penting maka sekumpulan wanita melakukan sebuah gerakan. “Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kumpul-kumpul. Karena disinilah tersimpan energi besar dan limpahan ide untuk melakukan hal besar secara bersama-sama. Ketika waktu begitu sempit untuk bertemu, bukan berarti kumpul-kumpul tidak bisa dilakukan melalui media yang berbeda, mailing list”. 15 Beginilah awal perkumpulan wanita yang bergerak bersama ini terbentuk. Mailing list (milis) tersebut merupakan wadah diskusi terkait permasalahan sekitar ASI dan mencari solusi yang relevan bersama-sama. Dukungan secara moril disampaikan, berbagi pengalaman membuat mereka merasa berada di tempat yang nyaman. Tanpa sadar, ruang maya membuat ikatan yang emosional diantara mereka. Milis ini semakin berkembang dan memberi ide untuk bertemu tatap muka sesama anggotanya. Pertemuan tersebut melahirkan banyak ide dan wacana. Semangat dari dan untuk ibu menyusui ini melahirkan sebuah gerakan. Gerakan yang kemudian melahirkan organisasi, AIMI. Organisasi nirlaba diluar pemerintah sebagai bentuk tindakan kolektif untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat terkait pentingnya ASI dan ancaman gagal menyusui. Sampai dengan tahu 2016 eksistensi AIMI semakin diakui, aktivitas dalam melindungi, mempromosikan dan mendukung kegiatan menyusui terlihat dari berbagai daerah sampai dunian internasional. Bahkan membentuk Koalisi Advokasi ASI yang beranggotakan AIMI, WHO, MERCY CORPS, SELASI, PERINASIA, HKI, KAKAK, Klasi-YOP, IBCLC Indonesia, dan YLKI. Koalisi ini terbentuk karena belum banyak pihak yang memahami tentang keunggulan menyusui dan pemberian ASI pada 12 http://www.seputarpengetahuan.com/2015/11/15-pengertian-norma-menurut-para-ahli-terlengkap.html Rachmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktik Riset komunikasi, Kencana, Jakarta 14 Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, PT Rajagrafindo Persada, Depok. 15 Adenita, Breastfriends Inspirasi 22, 2013, Buah Hati, hal 25 13 81 bayi. Belum bayak pula yang mengetahui resiko dari pemakaian susu formula dan bahwa terdapatnya peraturan yang mengatur pemasaran dari produk-produk pengganti ASI. AIMI merupakan wujud dukungan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam BAB VI tentang Dukungan Masyarakat Pasal 37 ayat (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Ayat (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu: a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusu dini ketika persalinan; b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir; c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya; d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI; e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui; f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja; g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun; h. menghormati ibu menyusui di tempat umum; i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui. Laporan Worlds Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) 2012, angka menyusui Indonesia rangking 49 dari 51 negara. 82 Sumber : http://www.worldbreastfeedingtrends.org Di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 10.457 bayi dari total 33.623 bayi yang belum mendapatkan kesempatan untuk menyusu secara eksklusif pada ibunya atau sebesar 68,8%. Walaupun angka ini relatif lebih baik dari daerah lain di Indonesia tetapi sebanyak 10.457 bayi masih perlu diperjuangkan haknya. Data lain menyebutkan durasi menyusui semakin bertambah usia bayi semakin pendek. Sementara rekomendasi WHO menyusui dilanjutkan sampai dengan bayi berusia 2 tahun. Tentu saja kekhawatiran para aktivis ASI banyak bayi atau anak berusia diatas 1 tahun yang belum genap berusia 2 tahun belum mendapatkan asupan yang sesuai dengan standar WHO. AIMI SUMBAR menjadi cabang ke 14 di Indonesia, dimulai dengan dibentuknya kelompok pendukung ASI tahun 2013, AIMI SUMBAR diresmikan tahun 2015. Peresmian ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Ibu Walikota Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pemerintah Kota Padang sedang menyusun Rancangan Perda. Setelah hampir setahun diresmikan, AIMI SUMBAR melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan rutin berupa Kelas Edukasi Menyusui sebagai upaya sosialisasi dan perayaan peringatan ASI baik di tingkat nasional maupun internasional. Kendala yang dihadapi dalam setiap kegiatan hampir sama dengan cabang-cabang lain di daerah yang tersebar di Indonesia. Donatur tetap serta negatif list sponsor untuk kegiatan membuat organisasi ini memiliki keterbatasan dalam mengkampanyekan ASI di Sumatera Barat. Sehingga para penggiat AIMI SUMBAR harus menemukan cara untuk mengkampanyekan visi dan misinya. Media massa adalah sarana yang dipilih untuk mengkampanyekan visi dan misi tersebut. “It has already been noted that social movements depend on the media to get their message across”. Media massa memainkan peran sebagai arena utama untuk mengekspresikan opini publik dan pembentukan opini publik. AIMI SUMBAR memanfaatkan semua jenis media online yang ada yaitu media cetak, media elektronik dan media online. Selama shampir satu tahun kampanye ASI di Sumatera Barat, AIMI SUMBAR telah muncul di beberapa media antara lain: 1. Media Cetak 83 84 85 2. Media Elektronik a. Radio 86 87 b. Televisi 88 Metro TV 89 3. Media online 90 Selain pemberitaa tersebut diatas AIMI SUMBAR berkerjasama dengan RRI Padang sebagai radio yang menjangkau berbagai kalangan. Program dua migguan “Beranda Perempuan” diisi oleh narasumber dari AIMI SUMBAR. Hasil wawancara dengan RRI Padang, kerjasama dengan AIMI SUMBAR tidak dikenakan biaya karena dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menyukseskan program ASI Eksklusif. Sejauh ini, hasil kerjasama dengan AIMI SUMBAR memberikan tanggapan yang beragam dari masyarakat dan pihak RRI antusias dan mendukung gerakan wanita ini. Salah satu materi sebagai hasil kerjasama ini adalah: 91 Untuk menyampaikan isu pesan yang berlawanan di masyarakat, teknologi memfasilitasi hal ini dengan pemanfaatan internet (Porta:2006). Karena keterbatasan dana, AIMI SUMBAR memulai gerakannya menggunakan media internet sebagai media yang paling mudah dan murah saat ini. Sumber : Profil Pengguna Internet Indonesia 2014 Pengguna internet di Indonesia menurut Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM UI) bekerjasama dengan Asosiasi Penyeleggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Profil Pengguna Internet Indonesia 2014 mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta dari 250jutaan jumlah penduduk Indonesia.16 Yang dilakukan kebanyakan orang saat terkoneksi ke internet adalah menggunakan jejaring sosial sebanyak 87,4%. Dan mayoritas pengguna internet adalah kaum wanita yaitu sebanyak 51%. Usia pengguna internet terbanyak 26-45 tahun sebanyak 16 Puskakom UI, Profil Pengguna Internet Indonesia 2014, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 92 48.4%. 84% pengguna internet menggunakan internet sekali sehari atau lebih. (www.puskakomui.or.id). Sebanyak 87.8% pengguna internet di Sumatera menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Di Sumatera Barat, sebanyak 1,8 juta menggunakan internet atau sebesar 35%. pengguna internet 43% berjenis kelamin wanita. 93 Sumber : Profil Pengguna Internet Indonesia 2014 Facebook sebagai media yang menyentuh segala lapisan pada saat ini menjadi sasaran. Seiring perjalanannya akun media lain juga dibuat seperti twitter, instagram dan telegram. Hal ini sesuai dengan temuan Puskakom UI sebanyak 87.8% pengguna internet di Sumatera menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Di Sumatera Barat, sebanyak 1,8 juta menggunakan internet atau sebesar 35%. Pengguna internet 43% berjenis kelamin wanita Akun facebook menjadi andalan sebagai wadah menyampaikan informasi. Sampai dengan bulan April 2016 akun facebook AIMI SUMBAR memiliki 1.423 teman. Grup facebook sebagai wadah konsultasi memiliki 617 orang anggota. Grup sebelumnya berjumlah lebih dari 2.000 anggota, hanya saja karena ketentuan untuk membuat akun media yang baru yang sesuai dengan rules AIMI, maka grup ini mulai dibentuk kembali setelah resmi menjadi cabang. Selain itu terdapat 110 penyuka fanpage AIMI SUMBAR Shop sebagai wadah jual beli seputar perlengkapan ASI dan kebutuhan lainnya. Fanpage ini juga bertujuan sebagai lahan mencari dana untuk keperluan organisasi. Selain facebook, twitter dengan 117 follower, Instagram dengan 290 follower dan yang baru dibuat sejak bulan Maret Maret 2016 telegram dengan 32 member. Semua akun 94 media sosial dibuat dengan tujuan mendapatkan perhatian masyarakat di berbagai ruang media yang ada di era web saat ini. Pada bulan April 2016, AIMI SUMBAR membuka kesempatan bagi warga provinsi Sumatera Barat untuk ikut menjadi bagian dari pengurus AIMI. Penerimaan calon pengurus ini dengan cara mendaftar secara online. Ditemukan peminatnya berjumlah 55 orang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jumlah ini yang lebih banyak dari penerimaan calon pengurus AIMI Sumatera Utara yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Dari data calon pengurus diketahui calon pengurus yang mengetahui informasi seputar AIMI SUMBAR dari facebook sebanyak 40 orang, dari instagram 1 orang, dari televisi 2 orang dan sisanya dari sumber lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu klien AIMI SUMBAR informasi terkait AIMI SUMBAR didapatkan dari postingan akun AIMI SUMBAR yang diposting ulang oleh rekannya. Klien tersebut menghubungi konselor AIMI SUMBAR karena terkendala saat pemberian ASI kepada bayinya yang berusia 11 hari dan dirawat di NICU, Klien lain menyebutkan, informasi terkait AIMI SUMBAR didapatkan dari siaran radio. Ketua AIMI SUMBAR menyampaikan masyarakat hendaknya mendukung ibu menyusui dimana saja dan kapan saja. Kampanye ASI diharapkan mengembalikan menyusui sebagai hal alami. Dan berbagai pihak dapat memperhatikan hak-hak ibu dan bayi agar ibu yakin menyusui walau masih terkendala berbagai hal misalnya ruang menyusui yang belum tersedia di ruang publik. Masyarakat sebagai support system dapat mendukung kampanye ini dengan menganggap menyusui adalah hal yang normal. Menyusui adalah proses pemberian makan dari ibu ke bayi. Realitas diatas sesuai dengan teori Norma Budaya atau The Cultural Norms Theory dari Melvin L DeFleur bahwa media massa secara selektif menyajikan dan menekankan ide-ide, nilai-nilai atau norma-norma dengan memperkuat atau mengubahnya. Maka AIMI SUMBAR menggunakan peran media dalam menyampaikan informasi dan mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam berbagai bidang. Penyajiannya dan penekanannya pada tema tertentu yaitu tema pemberian ASI kepada bayi dapat menciptakan kesan pada khalayak dengan memberikan bobot seperti manfaat ASI bagi berbagai pihak. Sehingga norma atau standar perilaku dalam masyarakat dapat menerima dan mendukung pemberian ASI dan berpartisipasi mendukung gerakan ini. Pemanfaatan media sosial dalam mengkampanyekan ASI menjadi sasaran karena dapat dirasakan langsung manfaatnya. Serta para aktivis AIMI SUMBAR dapat terhubung langsung dengan khalayaknya seperti konsultasi di grup facebook AIMI SUMBAR. Beberapa hasil konsultasi tersebut: 95 96 Sumber: grup facebook AIMI SUMBAR https://www.facebook.com/groups/aimisumbar/?ref=ts&fref=ts# Kondisi ini menggambarkan bertambahnya pengetahuan masyarakat terkait pemberian ASI. Bahkan anggota grup yang bukan pengurus AIMI SUMBAR dapat ikut serta memberikan saran terhadap permasalahan ibu dengan merujuk kepada dokumen yang ada di grup. Edukasi dan sosialisasi AIMI dengan memanfaatkan media sosial dapat terus dilakukan. Teori norma budaya menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan AIMI SUMBAR dengan melibatkan media yang ada diharapkan mampu mengubah perilaku khalayaknya agar menjadikan menyusui sebagai gaya hidup yang sesuai dengan kearifan lokal sehingga persentase angka ibu meyusui di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia umumnya dapat mencapai target MDGs yaitu 80%. 5.KESIMPULAN Gerakan sosial dukung ibu menyusui yang dikampanyekan oleh AIMI Cabang Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan persentase ibu menyusui di Sumatera Barat. 97 Pentingnya pemberian ASI sesuai rekomendasi WHO membutuhkan dukungan masyarakat, tidak cukup peran pemerintah saja, tapi dukungan setiap orang. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan finansial, emosional, praktikal, pengawasan dan sosial. Rendahnya pemberian ASI menurut peneitian sebelumnya karena kurangnya dukungan sosial ekonomi. Masih banyak bayi di Sumatera Barat belum mendapatkan kesempatan untuk menyusu secara eksklusif pada ibunya. AIMI SUMBAR sebagai jaringan organisasi yang merupakan bagian dari sebuah gerakan sosial mengkampanyekan dukungan terhadap ibu menyusui di Sumatera Barat dengan melibatkan media massa. Dari ketiga media yang digunakan AIMI, media sosial. Selain itu, media baru pun menjadi pilihan utama karena lebih praktis dan low cost. Diharapkan metode ini mampu mengubah perilaku masyarakat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi bayi dan ibu. Teori Norma Budaya menjelaskan dan memperkuat upaya AIMI SUMBAR mengkampanyekan ASI dengan pemanfaatan media massa. Diharapkan peran media mampu menjadikan menyusui dimanapun dan kapanpun menjadi norma di masyarakat Sumatera Barat. Tentu saja dukungan menyusui yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan orang sekitar baik saat hamil maupun setelah melahirkan sangat membantu ibu untuk menyusui anaknya sesegera dan selama mungkin, tetapi dukungan dari masyarakat sekitar cukup dapat membuat ibu yakin dan percaya diri dalam memberikan ASI kepada bayinya. Inilah bentuk support system untuk generasi yang lebih baik. “Succes in breastfeeding is not the sole responsibility of a woman, the promotion of breastfeeding is a collective societal responsibility” ~The Lancet~ 6.DAFTAR PUSTAKA Adenita. 2013. Breastfriends Inspirasi 22. Tangerang : Buah Hati. Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Anton Baskoro. 2008. ASI Panduan Praktis Ibu Menyusui. Banyu Media. Yogyakarta. Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Brent D Ruben, dkk. 2013. Komunikasi dan Perilaku Manusia. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada. DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. 1989. Theories of mass communication (5th ed.). White Plains. NY. GA Ohorella dkk.1992. Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2010. Indonesia Menyusui. Jakarta: Badan Penerbit IDAI. Jack Newman. 2008. The Ultimate Breastfeeding Book of Answers. Harper Collins Publisher Ltd. Canada. Mc Carthy John etc. 2015. The Social Movement Reader cases and Concepts. Wiley Blackwell. UK Muda, Deddy Iskandar. 2005. Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Peter Van Aelststefaan Walgrave. 2005. Cyberprotest new Media, Citizens and Social Movement. Routledge. London Porta D.D etc.2006. Social Movements an Introduction. Blackwell Publishing. Australia Rachmat Kriyantono. 2006. Teknik Praktik Riset komunikasi. Jakarta: Kencana. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. AIMI.2014. Materi Kelas Edukasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kemenkes RI. 2014. Pusat Data informasi Kementrian Kesehatan RI, Situasi dan Analisis ASI Eksklusif. 98 Peter Stalker. 2008. Millenium Development Goals. Puskakom UI. Profil Pengguna Internet Indonesia 2014. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Logan, Chad.etc. 2015. Changing Societal and Lifestyle Factors and Breastfeeding Patterns Over Time. PEDIATRICS Volume 137 , number 5 , May 2016 :e 20154473 Made Arini Hanindharputri. 2014. Tokoh Men Brayut Sebagai Ilustrasi Ikon Media Kampanye Asi Eksklusif Bagi Ibu Bekerja. Institut Seni Indonesia Denpasar. Yulien Adam dkk. 2012. Determinan Pemberian Asi Ekslusif Di Wilayah Puskesmas Telaga Biru dan Puskesmas Mongolato Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2012, Jurnal Unhas.http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d0816d1d5f891249ac679ff93b0741ba. pdf diakses pada 11 April 2016 http://themilkmeg.com/ingredients-in-breastmilk-versus-artificial-breastmilk-formula/ diakses pada tanggal 17 April 2016 http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21270.html diakses pada tangal 17 April 2016 http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21270.html diakses pada tanggal 20 April 2016 http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-media-massa-definisi-fungsi.html diakses pada tanggal 25 April 2016 https://ethicsinpr.wikispaces.com/Cultural+norms diakses pada tanggal 25 April 2015 http://www.seputarpengetahuan.com/2015/11/15-pengertian-norma-menurut-para-ahliterlengkap.html diakses pada tanggal 25 April 2016 http://m.metrotvnews.com/video/good-news-today/eN4vnZ5k-manfaat-asi-bagi-bayi-danibu http://m.metrotvnews.com/play/2016/04/21/516962 diakses pada tanggal 25 April 2016 http://sumbar.antaranews.com//berita/175380/aimi-sumbar-gelar-kegiatan-menyusuiserentak.html diakses pada tanggal 25 April 2016 https://www.youtube.com/watch?v=IQC3ZVD9pok diakses pada tanggal 25 April 2016 http://www.antarasumbar.com/berita/150140/aimi-sumbar-resmi-dikukuhkan-dipadang.html diakses pada tanggal 25 April 2016 http://www.antaranews.com/berita/536137/aimi-sumbar-gelar-selebrasi-hari-ibu diakses pada tanggal 25 April 2016 http://aimi-asi.org/about/ https://www.facebook.com/groups/aimisumbar/?ref=ts&fref=ts# www.puskakomui.or.id 99 MENOLAK UNTUK MENYERAH: UPAYA PEREMPUAN PERAJIN BATIK TULIS UNTUK TETAP MENJAGA TRADISI BATIK TULIS DI KABUPATEN BANJARNEGARA 1 Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si, 2 Dr. Riris Ardhanariswari, SH, MH. 1 Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed, Email:[email protected] 2 Fakultas Hukum Unsoed Email:[email protected] Abstrak Nasib para perajin batik tulis tidak seindah kain yang dihasilkannya. Hubungan kerja antara perajin dan juragan yang bercorak putting-out system cenderung merugikan perajin yang umumnya perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi para perajin batik tulis di Kabupaten Banjarnegara serta upaya yang mereka lakukan untuk tetap bertahan menghidupkan tradisi batik tulis, sekaligus hidup dari tradisi tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi para perajin membatik bukan sekadar bekerja mencari penghidupan. Lebih dari itu, membatik adalah menjaga tradisi turun temurun. Mereka menghadapi banyak persoalan terkait hubungan kerja dengan juragan yang timpang. Selain menerima upah yang rendah, mereka juga harus menanggung hampir semua risiko kerja. Di sisi lain, ketergantungan mereka kepada juragan sangat tinggi, terutama terkait pengadaan bahan baku dan pemasaran. Selain itu, serbuan batik cap dan tawaran upah yang lebih tinggi dari industri bulu mata turut menjadi ancaman. Bertolak dari kondisi tersebut, para perajin sepakat membentuk kelompok sebagai rintisan koperasi. Melalui kelompok ini, mereka berharap tetap dapat menghidupi tradisi dan hidup dari tradisi. Kata Kunci: Tradisi, Batik, Perajin, Juragan, Perempuan Abstrac The fate of the batik tulis crafters is not as beautiful as their works. The working relationship between the artisans and the skipper is patterned putting-out system which generally tends to disadvantage women artisans. The purpose of this study is to identify the problems faced by thebatik tulis artisans in Banjarnegara District and their efforts to revive batik tulis tradition, and getting prosperous life from this tradition. The study used a qualitative approach. Informants selected using purposive sampling technique and data collected by interviews, documentary studies, and observations. The results showed that for the batik artisans,making batik is not only to make a living. Moreover, making batik is about keeping the tradition. They face a lot of problems related to disadvantage working relationships with skipper. Besides, receiving low wages, they also have to bear almost all occupational risks. On the other hand, their dependence on the skipper is very high, especially related to raw material procurement and marketing. In addition, the invasion of batik cap and offer higher wages from the fake lashes industry also become a threat. Starting from these conditions, the artisans have agreed to start up groups to establish a cooperative. Through this group, they hope they can still keep the traditions and make a living from it. Keywords: Tradition, Batik, Artisans, Skipper, Female 1.PENDAHULUAN 100 Sebagai warisan budaya Indonesia yang sangat berharga, batik kembali menjadi sorotan setelah pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCOmenetapkan batik sebagai “warisan budaya tak benda” milik Indonesia.Tanggal tersebut kemudian ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hari Batik Nasional.Momentum tersebut menjadi menjadi salah satu pemicu geliat industri batik di Tanah Air. Industri batik berkembang di berbagai kota di Pulau Jawa, terutama di Solo, Jogjakarta, dan Pekalongan, dengan beragam motif dan corak sesuai karakteristik daerah masing-masing. Misalnya, batik banyumasan menggambarkan kehidupan agraris dan karakter masyarakat Banyumas yang suka cablaka, juga berisi nasihat-nasihat (Rochmawati, 2010). Di luar ketiga daerah tersebut, batik juga menyebar di berbagai daerah dan kota, seperti Sumatera, Madura, Cirebon, Lasem, dan Banyumas. Industri batik juga berkembang di Kabupaten Banjarnegara. Industri batik di Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan varian batik banyumasan, terpusat di Desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon yang secara administratif termasuk Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Kedua desa tersebut letaknya berdampingan,karena pada zaman dulu desa tersebut merupakan wilayah Kademangan Gumelem di bawah Kerajaan Mataram pada era 1573 M. Kerajinan batik yang dimiliki oleh masyarakat Gumelem ditularkan oleh keluarga kademangan. Saat ini Desa Gumelem Wetan memiliki 170 perajin batik dan 2 juragan batik, sedangkan Desa Gumelem Kulon memiliki 50 perajin batik dan 3 juragan batik (Ardhanariswari, 2014). Sebagai industri yang berbasis pada tradisi yang mengakar, industri batik selayaknya menjadi social-economic capital yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namunterbatasnya pemasaran dan adanya ancaman batik printing membuat perkembangan industri batik gumelem kurang optimal. Selain kedua masalah tersebut, industri batik gumelem juga belum diikuti oleh kesejahteraan para perajinnya. Hubungan kerja yang bercorak putting-out system membuat posisi perajin batik sangat terpinggirkan. Tulisan ini akan fokus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi para perajin batik tulis di Kabupaten Banjarnegara serta upaya yang mereka lakukan untuk tetap bertahan menghidupkan tradisi batik tulis, sekaligus hidup dari tradisi tersebut 2.TINJAUAN PUSTAKA Perempuan Perajin Batik Tulis dalam Putting-out System Hubungan buruh dan majikan dalam industri batik telah lama diwarnai hubungan kerja yang bercorakputting-out system(Chotim, 1994).Putting-out system merupakan cara kerja produksi barang dengan pelaksanaan produksi di rumahpekerjanya, sementara bahan kerja dan alat produksi dicukupi oleh pemilik usaha. Pemilik usaha melakukan kontrol kualitas, membayar upah produksi, tetapi tidak menanggung risiko pekerjaan, termasuk kesehatan dan jaminan sosial lainnya bagi pekerjanya (Syaifudian dan Chotim, 1994). Sementara Suratiyah (1997) mendefinisikan putting-out system sebagai sistem untuk mengatur, mengendalikan, dan memobilisasi proses produksi dan hubungan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dilakukan di luar perusahaan. Pekerjaan dari perusahaan dibawa dan dikerjakan oleh pekerja ditempat yang dipilih sendiri, biasanya di rumah atau disekitar rumah pekerja. Pekerja dalam hal ini dikategorikan dalam pekerja rumahan, yaitu tenaga kerja yang menerima pekerjaan dari pengusaha tanpa ikatan kerja formal, membawa dan menerima kerja, menanggung sendiri risiko produksi serta menerima upah kerja berdasarkan satuan output (borongan) menurut ukuran sang pengusaha. Menurut Mas’oed (2006), sistem kerja putting-out system lebih banyak memberi keuntungan bagi majikan karena majikan tidak perlu menyediakan tempat kerja. Para majikan lepas dari keharusan menjamin keselamatan kerja dan berbagai perlindungan lain 101 yang seharusnya diterima oleh buruh. Selain itu, mereka bisa memperoleh hasil dari pekerjaan buruh ekstra, yang sebenarnya tidak terlibat kontrak, misalnya anggota keluarga di rumah.Sebaliknya, bagi tenaga kerja sistem putting-out system lebih banyak merugikan dikarenakanmeniadakan perlindungan bagi buruh, misalnya keselamatan kerja maupun jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Selain itu, dapat terjadi pelanggaran hak asasi anak karena pengerjaan dirumah memungkinkan keterlibatan buruh anak. Dalam putting-out system, pekerjaan dari majikan dikerjakan oleh pekerja di rumah sendiri sehingga dapat dikategorikan sebagai pekerjaan rumahan.Ciri pekerjaan rumahan(home based production)antara lain: (1)tidak memerlukan skill yang tinggi; (2) bisa dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;(3)bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat (harian-mingguan); (4).modal tidak besar dan; (5) umumnya dilakukan oleh kaum perempuan. Sistem kerja dengan membawa pekerjaan kerumah dengan model putting-out system biasanya berlaku di daerah-daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan kurang mampu dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Kondisi tekanan ekonomi mengharuskan mereka melakukan kerja sambilan, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif sekaligus produktif. Pekerja rumah masuk dalam sektor informal, yaitu pekerja yang bekerja dengan cara tidak tetap; sistem pengupahan borongan; merupakan pekerjaanpekerjaan pinggiran, sehingga kebanyakan dilakukan oleh perempuan (Hart, 1989). Hubungan kerja pada industri batik di Kabupaten Banjarnegara juga bercorak putting-out system (Ardhanariswari, 2014) di mana posisi pemilik usaha (juragan) sangat dominan. Juraganmenentukan harga bahan baku dan upah produksi. Mereka juga menetapkan standar kualitas sehingga dapat menolak hasil produksi perajin yang tidak sesuai standar baku mutu. Juragan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak apabila volume pekerjaan turun tanpa harus memberikan kompensasi kepada perajinnya. Sebaliknya, posisi perajin sangat lemah. Selain upah ditetapkan secara sepihak oleh juragan, para perajin harus menanggung risiko jika produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan juragan. Perajin tidak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan kerja. Mereka harus menerima risiko kesehatan, seperti terkena ISPA atau tertuang malam panas, selain risiko tidak adanya jaminan kepastian kerja. Putting-out system sekilas tampak menguntungkan pekerja -terutama bagi ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga - karena relatif fleksibel. Jam kerja ditentukan oleh pekerja sendiri, pekerja tidak harus kehilangan waktu dan ongkos untuk berangkat ke dan pulang dari tempat kerja, sementara sambil bekerja mereka tetap dapat melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun jika dicermati, sistem ini justru sangat menguntungkan pemilik modal karena selain (hampir) tidak menanggung risiko, mereka juga tidak perlu menyediakan tempat dan fasilitas pendukung seperti listrik dan alat produksi lainnya. Meskipun putting out system tidak menguntungkan bagi perempuan perajin batik tetapi kemiskinan dan kultur patriarkhi menyebabkan mereka menerima pekerjaan membatik dengan upah yang rendah. Memberdayakan Perempuan Perajin Batik Tulis Menurut Abdullah (1997), peran perempuan yang dalam struktur ekonomi menunjuk pada kecenderungan “pejajahan” laki-laki atas perempuan. Kecenderungan ini mengarah pada dua implikasi. Pertama, pergeseran struktur ekonomi makro secara langsung menggeser kaum perempuan. Ketikakesempatan kerja kaum laki-laki berkurang, mereka mengambil alih dan melakukan ekspansi ke sektor yang semula dikuasai perempuan. Disini perempuan dikalahkan dan/atau bahkan mengalah. Kedua, perubahan struktur ekonomi secara langsung membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena segmentasi pasar yang semakin rumit. Jika ada peluang maka 102 laki-laki adalah prioritas, jika peluang terbatas mereka mendesak dan melakukan marginalisasi terhadap perempuan. Kalau pun perempuan dipekerjakan, biasanya lebih didasari kebutuhan “tangan perempuan” dengan alasan memaksimalkan keuntungan, karena mempekerjakan perempuan sama dengan mendapatkan tenaga berupah murah. Fakih (1997) menegaskan, proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termaginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis kelamin. Perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Sebagai contoh dalam hal pekerjaan. Perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga, maka perbedaan gaji pun diterapkan antara perempuan dan laki-laki. Kondisi yang dialami oleh perempuan perajin batik di Kabupaten Banjarnegara secara tidak langsung dipengaruhi kultur patriarkhi. Mereka meyakini bahwa pekerjaan membatik yang selama berpuluh tahun mereka lakukan hanyalah pekerjaan sampingan. Mereka menganggap pekerjaan utama perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman ini tentu saja berpengaruh terhadap penghargaan perempuan perajin batik terhadap pekerjaannya. Menganggap membatik sebagai pekerjaan sampingan membuat mereka merasa “layak” diupah murah. Pemberdayaan perlu dilakukan agar para perempuan, khususnya perajin batik, mau dan mampu memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka hasilkan. Penelitian ini memaknai pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di sektor-sektor kehidupan. Pemberdayaan juga merupakan proses memfasilitasi warga masyarakat pada sebuah kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan bersama, mengumpulkan sumberdaya, dan membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Masyarakat bawah dalam hal ini perempuan perajin batik. Untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang berdaya dapat dimodifikasi dari strategi pemberdayaan lapisan masyarakat bawah dari Tjokrowinoto (1987) sebagai berikut : a. Masyarakat bawah telah mampu menekan perasaan ketidakberdayaan bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. b. Setelah kesadaran kritis muncul, masyarakat dapat melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya. c. Masyarakat telah memiliki rasa kesetaraan dan meyakini bahwa kemiskian sebagai penjelmaan konstruksi sosial, bukan takdir. d. Masyarakat telah memiliki keberanian untuk melibatkan dirinya dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. e. Masyarakat dapat menyerap perubahan nilai positif seperti perencanaan hidup, optimisme, pola hidup, produktivitas dan kualitas kerja. 3.METODE PENELITIAN Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai pengalaman penelitian dan sifat permasalahan (Strauss dan Corbin, 1990). Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki kelebihan dalam mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya, serta memiliki fokus pada proses interaktif dan peristiwa (Newman, 1994). Pemilihan informan menggunakanteknikpurposive samplingdengan kriteria informan sesuai kebutuhan studi iniatau bersifat unik dari sesuatu yang akan diteliti(Harrison, 2007).Sasaran utama penelitian adalah para perempuan perajin batik tulis. Peneliti juga mewawancarai para 103 juragan, pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk validasi data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi (Punch, 2006). Analisis data menggunakan model analisis interaktif seperti yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992). Analisis dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Data yang terkumpul direduksi menjadi pokok-pokok temuan penelitian dan disajikan secara naratif untuk kemudian diinterpretasikan secara logis. Reduksi dan penyajian data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1.1. Sekilas Tentang Desa Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon Desa Gumelem Wetan berada di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Desa Gumelem Wetan seluas 805,278 ha.Sebagian besar wilayahnya berbukitbukit, beberapa bagian di antaranya rawan erosi, terutama di wilayah dusun IV dan dusun III.Penduduk Desa Gumelem Wetan sebesar 10.733 jiwa, terdiri dari 5.374 penduduk lakilaki (50,07 persen) dan 5.359 penduduk perempuan (49,93 persen) dengan jumlah kepala keluarga 2.711 KK. Hampir semua penduduk Desa Gumelem Wetan beragama Islam. Fasilitas peribadatan yang ada meliputi enam buah masjid dan 46 mushola. Namun seperti umumnya masyarakat petani yang masih lekat dengan berbagai ritus yang berkaitan dengan siklus tanam, masyarakat desa ini masih kental memegang tradisi jawa, salah satunya tradisi sadran gedhe yang diselenggarakan setiap menjelang bulan Ramadhan. Sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan, baik sebagai petani (729 orang atau 27,16 persen), buruh tani (293 orang atau 10,92 persen). Menariknya, banyak penduduk Desa Gumelem Wetan yang bekerja sebagai perajin, seperti perajin perajin pande besi, perajin ciri batu, dan batik tulis, bahkan batik gumelem sudah menjadi salah satu ikon budaya sekaligus ikon wisata Kabupaten Banjarnegara. Selain memiliki kreativitas tinggi dan dinamis, masyarakat Desa Gumelem Wetan juga dianugerahi bentang alam nan permai. Desa ini berada di lereng Gunung Wuluh dan Bukit Girilarangan, dialiri dua buah sungai dengan 16 mata air yang menghidupi warga desa, bahkan terdapat curug (air terjun) dan mata air panas. Di desa ini juga terdapat cagar budaya dan situs sejarah, yakni sebuah masjid kuno, makam keluarga demang, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Gumelem. Selain tradisi sadran gedhe, masyarakat desa ini memiliki kesenian tradisional ujungan. Desa Gumelem Kulon terletak di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Desa Gumelem Kulon sebesar 812,2 ha, sebagian besar merupakan dataran tinggi/pegunungan dan sisanya merupakan dataran rendah dan areal persawahan. Seperti halnya penduduk Desa Gumelem Wetan, hampir seluruh penduduk Desa Gumelem Kulon beragama Islam, namun demikian nilai-nilai tradisi Jawa masih cukup dominan. Umumnya masyarakat pedesaan, masyarakat Desa Gumelem Kulon banyak yang bekerja di sektor pertanian, sebagai petani atau buruh tani sawah. Desa ini juga dikenal sebagai sentra penghasil gula kelapa. Sayangnya, manisnya gula tidak semanis nasib petaninya. Harga gula yang fluktuatif, pohon kelapa yang sudah tua sehingga produktivitasnya menurun, banyaknya penderes yang terbelit sistem panjar (ijon) dari para tengkulak, serta banyaknya jalan yang rusak sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi, merupakan kendala yang harus dihadapi petani kelapa. 1.2. Pasang SurutPerkembangan Batik Gumelem 104 Batik gumelem sebagaimana disebutkan dalam buku Profil Batik Gumelem (2008), diyakini sudah ada sejak berdirinya Kademangan Gumelem. Saat itu, miniatur kehidupan istana seperti pranata, trapsila, busana, dan tata praja secara baik dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Kademangan Gumelem. Sebagai wilayah perdikan, Kademangan Gumelem mengatur rumah tangganya sendiri. Demang memiliki pembantu para sentana dalem yang mengurus kelancaran pemerintahan. Di samping itu, terdapat satuan-satuan kerja teknis pendukung dan penjaga kewibawaan kademangan, salah satunya adalah para tukang batik yang bertugas membuat kain batik bagi keperluan busana keluarga, kerabat, dan sentana dalem kademangan. Sejarah perkembangan batik gumelem tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kademangan Gumelem. Masa keemasan batik gumelem mengalami penurunan sejalan dengan berubahnya status kademangan yang awalnya merupakan tanah perdikan (bebas pajak) di bawah pengaruh Kasunanan Surakarta menjadi desa praja. Wilayah kademangan pun kemudian dibagi dua menjadi Gumelem Wetan dan Gumelem Kulon. Status dan wilayah kademangan berubah karena Surakarta dilanda krisis politik dan pemerintahan. Runtuhnya Kademangan Gumelem menjadi pukulan berat bagi perkembangan batik gumelem. Batik sebagai kebudayaan kalangan istana yang selama ini bertahan karena perlindungan kalangan kademangan runtuh perlahan akibat berkurangnya kebutuhan batik karena berkurangnya jumlah sentana dalem, serta acara pemerintahan dan ritual adat yang biasa dilakukan.Surutnya masa keemasan batik gumelem juga disebabkan lunturnya nilainilai sakral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Batik semakin kehilangan mitos dan filosofi yang terkandung di dalamnya, tinggal menjadi semacam ragam hias yang mengandalkan unsur keindahan belaka. Di sisi lain, batik mulai dianggap sekadar bagian dari industri sandang. Sejak runtuhnya kademangan, batik gumelem pun mengalami kelesuan panjang. Kain batik hanya digunakan oleh perempuan tua sebagai pakaian tradisional sehari-hari (jarit/jarik), selendang penggendong bayi, atau kain penutup jenazah. Kain pun hanya diproduksi ulang melalui teknik cetak (printing) agar harga terjangkau. Para pembatik tulis pun semakin jarang ditemukan dan nyaris punah. Tahun 2003 dapat disebut sebagai tahun kebangkitan batik gumelem, ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Banjarnegara agar setiap hari Sabtu, PNS seKabupaten Banjarnegara menggunakan batik gumelem saat melaksanakan tugas. Surat edaran ini ternyata cukup jitu untuk menggairahkan kembali industri batik gumelem yang mati suri. Industri tersebar di empat desa, yaitu Desa Gumelem Wetan, Gumelem Kulon, Panerusan Wetan, dan Susukan. Selain menerbitkan surat edaran, melalui Dekranasda, Pemkab Banjarnegara melakukan berbagai terobosan untuk nguri-uri batik gumelem dengan berbagai upaya, seperti pelatihan melalui sistem magang, pemberian bantuan peralatan pembuatan batik tulis dan batik cap, pelatihan pewarnaan, teknik pembuatan batik cap dan desain motif batik, lomba rancang motif dan busana batik gumelem setiap dua tahun sekali, studi banding untuk membuka wawasan perajin, serta pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah/subsidi bunga. Perhatian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat setelah adanya pengakuan UNESCO bahwa batik merupakan Warisan Bukan Benda Asli Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Sehari setelah pengakuan UNESCO tersebut - yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional - keluarlah surat edaran yang mewajibkan seluruh PNS se-Kabupaten Banjarnegara selama seminggu penuh mulai tanggal 5-10 Oktober 2009 menggunakan batik selama jam kerja.Tak berapa lama kemudian turun Keputusan Bupati Nomor: 025/ 591 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab Banjarnegara. Salah satu poin pentingnya adalah penggunaan pakaian batik diperpanjang dari semula hanya hari Sabtu, menjadi tiga hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan 105 Sabtu. Sejalan dengan waktu, kini aturan pemakaian batik diperpanjang lagi menjadi empat hari dalam seminggu, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 1.3. Kendala yang Dihadapi Para Perempuan Perajin Batik Tulis Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi para perempuan perajin batik gumelem sebagai berikut. a. Tidak ada perjanjian kerja secara tertulis.Hubungan antara pekerja dengan juragan adalah kepercayaan karena tidak ada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Dalam model hubungan kerja bercorak putting-out system yang terjadi antara juragan dan perajin batik gumelem tidak ditemukan adanya perjajian kerja secara tertulis,bahkan “kesepakatan kerja” sepenuhnya ditentukan juragan.Tidak adanya perjanjian kerja yang tertulis mengakibatkan kedudukan antara pekerja, dalam hal ini perempuan perajin batik, dengan pengusaha/juragan tidak seimbang, dimana juragan dalam posisi dominan.Meskipun merupakan pekerja rumahan, perempuan perajin batik seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan UU Ketenagakerjaaan, selain mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya seorang pekerja/buruh. b. Sistem pengupahan ditentukan secara sepihak oleh juragan.Perempuan perajin batik mempunyai bargaining power yang lemah terutama berkaitan dengan upah yang diperolehnya. Besaran upah ditentukan “kemurahan hati” juragan. Upah dihitung per lembar kain, yakni antara Rp 20.000 – Rp 50.000 per lembar yang dapat diselesaikan 2-3 hari, bahkan lebih, tergantung kerumitan motif. Jika diratarata, upah pekerja antara Rp 7.500 – Rp 20.000 per hari, sementara UMK Banjarnegara tahun 2015 sebesar Rp 1.112.500 per bulan. Artinya, upah buruh batik tulis jauh di bawah upah minimumyang ditetapkan pemerintah, padahal UMK Banjarnegara termasuk yang terendah di Provinsi Jawa Tengah.. c. Tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.Perempuan perajin batik pada umumnya tidak memiliki akses ke jaminan sosial dan tidak juga diberi tunjangan kesehatan oleh pengusaha/juragan. Apabila cedera karena kecelakaan kerja misal terkena malam yang panas pada saat membatik atau sakit, hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada bantuan. Semua tergantung “kemurahan hati” juragan. d. Keterbatasan akses terhadap bahan baku.Bahan baku utama dalam usaha batik tulis adalah malam (lilin) dan kain mori.Bahan baku ini belum tersedia di Banjarnegara dan harus dibeli di Banyumas, bahkan di Pekalongan. Hanya juragan yang mampu membeli bahan baku dalam partai besar sehingga harganya lebih murah. Bagi perajin yang ingin mandiri terpaksa membeli dengan harga lebih mahal karena harus mengeluarkan ongkos perjalanan. Akibatnya margin keuntungan yang mereka terima sangat kecil. Oleh karena itu, dalam pengadaan bahan baku banyak perajin yang lebih memilih tergantung pada juragan,sementara perlengkapan lainnya seperti kompor listrik, kompor minyak, kompor gas, atau tungkumereka sediakan sendiri. e. Produktivitas kerja belum stabil. Pekerja menganggap bahwa pekerjaan membatik ini adalah pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama.Rendahnya upah membatik yang mereka terima saat ini memaksa para perajin mencari pekerjaan lain yang lebih dapat mencukupi kebutuhan. Umumnya mereka bekerja di sektor pertanian. Menurut seorang informan, upah perempuan perajin batik sejak tahun 1942 hanya dapat untuk membeli beras dua kilogram yang apabila dikonversikan dengan nilai uang sekarang berkisar Rp 20.000. Jika demikian, saat ini upah perajin batik justru semakin merosot dibanding tahun 1940an. Akibat membatik bukan menjadi 106 f. g. h. i. pekerjaan utama, maka produktivitas kerja tidak stabil. Dalam wawancara, seorang juragan, Ibu Str, mengeluh tidak dapat memenuhi pesanan dalam jumlah banyak karena produktivitas pekerja fluktuatif, tergantung “waktu luang” yang ada. Mereka bekerja sekadar “daripada menganggur di rumah.” Jika musim tanam misalnya, para perajin memilih bekerja di sawah karena upahnya lebih tinggi. Menurut Ibu Wtr, kalau tandur sehari dapat upah sebesar Rp 45.000 dengan jam kerja mulai jam 05.30-11.30, sedangkan kalau membatik dari jam 09.00-16.00 itu juga belum dapat selembar kain karena satu lembar kain dikerjakan kurang lebih 2-3 hari dan upahnya hanya Rp. 30.000. Maraknya batik cap/printing. Selain menghadapi persoalan-persoalan di atas, para perajin batik tulis juga harus menghadapi serbuan batik cap/printing. Batik printing tidak menggunakan malam dan tidak menggunakan canthing, seluruhnya dikerjakan layaknya sablon seperti kain motif pada umumnya (http://www.batikgumelem.com, 2013).Berbeda dari batik tulis yang pengerjaannya sangat lama dan rumit serta membutuhkan kesabaran dan ketrampilan luar biasa, batik cap dapat diproduksi secara cepat dan masif. Pasar batik Tempo waktu pengerjaan yang lama ditambah kegiatan membatik masih dianggap pekerjaan sambilan, membuat batik gumelem sulit memenuhi permintaan pasar baik dari sisi harga maupun ketersediaan barang.Kondisi ini membuat pengusaha berpaling ke batik cap sehingga volume kerja batik tulis menurun. Akibatnya banyak perempuan perajin batik yang terpaksa menganggur. Pekerja batik cap umumnya laki-laki. Masuknya industri bulu mata palsu. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan perajin batik di atas patut menjadi perhatian dari pemerintah setempat. Ketika perajin batik menganggap pekerjaan membatik tidak lagi menguntungkan, mereka dapat meninggalkan pekerjaan tersebut. Kecenderungan seperti ini sudah mulai tampak. Beberapa perempuan perajin batik dari Desa Gumelem Wetan dan Desa Gumelem Kulon telahberalih pekerjaan menjadi buruh pembuatan rambut palsu dan bulu mata palsu (buruh ngidep) di perusahaan-perusahaan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga, bahkan ada perusahaan yang sudah memiliki plasma di Desa Gumelem. Selain tawaran upah yang jauh lebih tinggi (sekitar satu jutaan per bulan), jaminan kerja buruh ngidep juga lebih terjaga. Bagi kaum muda ngidep juga lebih prestisius karena tangan tetap bersih, tidak harus kotor terkena malam dan pewarna kain. Selain itu, ada beberapa pengusaha bulu mata yang berani memberikan pinjaman kepada buruhnya untuk kredit motor. Tentu saja tawaran ini menarik bagi mereka. Hal ini menjadi ancaman bagi upaya pelestarian batik sebagai warisan budaya yang membanggakan masyarakat Banjarnegara. Kurangnya regenerasi. Selain persoalan di atas, masa depan industri batik tulis gumelem juga terancam oleh sedikitnya kaum muda yang tertarik menjadi perajin batik tulis.Kegelisahan ini juga ditangkap Kepala Desa (Kades) Gumelem Kulon yang menyatakan bahwa selain masalah permodalan dan pemasaran, industri batik tulis gumelem juga semakin terancam punah karena pembatiknya sudah tua-tua. Harapannya banyak generasi muda yang tertarik membatik dan mengembangkannya.Pemkab Banjarnegara melalui Dinas Indagkop UMKMpernah melakukan pelatihan kepada generasi muda di Desa Gumelem Wetan dan Desa Gumelem Kulon untuk belajar membatik maupun memberikan bantuan alat untuk mencelup dan mewarnai batik, namun hasilnya hampir tidak ada. Rendahnya akses terhadap bantuan pemerintah.Pemkab Banjarnegara telah melakukan berbagai terobosan untuk nguri-uri batik gumelem dengan berbagai upaya, seperti pelatihan melalui sistem magang, pemberian bantuan peralatan 107 pembuatan batik tulis dan batik cap, pelatihan pewarnaan, teknik pembuatan batik cap dan desain motif batik, lomba rancang motif dan busana batik gumelem setiap dua tahun sekali, studi banding untuk membuka wawasan perajin, serta pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah/subsidi bunga.Namun bantuan dan pemkab dan pemprov justru menjadi aset elite lokal. Juragan menggunakan posisi mereka untuk memperoleh bantuan dari pemkab dan pemprov, sebaliknya premkab dan pemprov berdalih belum adanya kelompok atau paguyuban perajin mempersulit pemerintah dalam memberikan bantuan kepada perajin. j. Belum ada perkumpulan atau paguyuban perempuan perajin batik gumelem. Padahal dengan adanya paguyuban diharapkan dapat menyatukan para pembatik sehingga dapat meningkatkan bargaining power mereka di hadapan pengusaha/juragan.Selain itu, dengan adanya kelompok maka akan mempermudah para perajin dalam memperoleh bantuan pemerintah. 1.4. Melawan untuk Menyerah Berbagai persoalan yang dihadapi para perajin batik tulis sebagaimana dipaparkan di atas memunculkan wacana pengadaan batik printing dengan motif khas gumelem. Keunggulan batik printing tentu saja dari sisi efisiensi waktu karena tidak melalui proses penempelan lilin dan pencelupan seperti batik pada umumnya, hanya saja motif yang dibuat adalah motif batik sehingga batik printing bisa diproduksi dalam jumlah besar. Namun wacana ini tidak sepenuhnya mendapat sambutan baik, terutama dari perajin batik tulis. Mereka bersikukuh bahwa batik adalah kain yang ditulis atau dihias motif-motif khas dengan malam panas melalui canthing dan disempurnakan dengan proses pencelupan. Sementara batik printing tidak menggunakan malam dan tidak menggunakan canthing, seluruhnya dikerjakan layaknya sablon seperti kain motif pada umumnya sehingga tidak dapat disebut batik. Salah satu perajin batik yang tetap bertekad melestarikan batik tulis adalah Mbah M., nenek warga Desa Gumelem Kulon berusia lebih dari 80 tahun yang masih aktif membatik. Menurutnya, membatik bukan hanya soal mencari makan, tapi juga melestarikan tradisi. Nenek yang mulai membatik sejak Zaman Ratu Wilhelmina (tahun 1942) ini membatik tanpa menggunakan pola karena sudah hafal motif-motif batik gumelem. Hasil kerjanya pernah ditolak pihak pemesan karena dianggap kurang rapidan tidak sesuai pola. Namun Mbah M tetap bergeming karena menurutnya membatik bukan sekadar menorehkan malam cair di atas kain mori yang sudah diberi pola, lebih dari itu, membatik adalah ekspresi jiwa sehingga setiap lembar batik tulis selalu berbeda, meski motifnya sama. Kekerasan hati Mbah M menurun kepada putri ragilnya, Mbak Ng. Di antara sepuluh bersaudara, hanya dia yang tetap setia mewarisi tradisi membatik. Dalam kehidupan serba pas-pasan, Mbak Ng tetap setia membatik. Dia sangat prihatin dengan semakin berkembangnya batik printing – yang ironisnya justru difasilitasi oleh Pemkab. Banjarnegaramelalui pemberian bantuan peralatan dan pelatihan batik printing kepada beberapa juragan, padahal batik tulis gumelem merupakan ikon Kabupaten Banjarnegara. Mbak Ng juga prihatin dengan semakin sedikitnya generasi muda yang terjun membatik. Mereka lebih suka menjadi buruh ngidep yang menawarkan upah jauh lebih tinggi. Keinginannya yang besar untuk mandiri membuatnya bertekad memproduksi batik dan memasarkannya sendiri ke langsung konsumen. Perjumpaannya dengan konsumen dari berbagai kalangan membuat pandangannya maju dan wawasannya terbuka. Di Gumelem Wetan ada Mbak Wr, perempuan berparas ayu yang membatik sejak kecil. Keahliannya dalam membatik membuatnya sering diminta oleh beberapa sekolah untuk mengajari siswa membatik, juga diminta mengajar di tempat-tempat lain. 108 Interaksinya dengan dunia luar membuatnya berpikiran maju. Seperti halnya Mbak Ng, Mabak Wr juga memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri, hanya saja dia merasa ewuh dengan juragan yang selama ini sudah memberinya pekerjaan. Mengatasi perasaan sungkan tersebut, Mbak Wr membuat terobosan dengan membuat batik tulis menggunakan pewarnaan alam. Difasilitasi tim peneliti, Mbak Ng dan Mbak Wr bersama beberapa perempuan perajin batik dari kedua desa dipertemukan dengan pendamping dan pengelola Koperasi Nira Kamukten, sebuah paguyuban para penderes kelapa dari wilayah Gumelem dan sekitarnya yang telah berhasil membuat koperasi. Akhirnya para perempuan perajin bersepakat untuk membuat kelompok sebagai langkah awal membentuk koperasi, yakni Kelompok Giri Alam dari Desa Gumelem Wetan yang diketuai Mbak Wr dan Kelompok Pandan Sari dari Desa Gumelem Kulon yang diketuai oleh Mbak Ng. Kelompok Giri alam fokus menggarap batik tulis dengan pewarna alami, sementara Kelompok Pandan Sari fokus menggarap batik tulis dengan motif gumelem. Dengan berkelompok mereka dapat lebih mandiri karena peluang untuk mengakses bahan baku murah dan pasar lebih terbuka. Demikian juga akses terhadap bantuan pemerintah yang selama ini “dibajak” para juragan. Dalam kondisi demikian, mereka berharap tetap dapat menghidupi tradisi dan hidup sejahtera dari tradisi yang mereka kukuhi. Kelompok perajin batik yang telah terbentuk masih membutuhkan penguatan organisasi agar nantinya mereka dapat membentuk koperasi. Tapi setidaknya langkah awal ini membuktikan bahwa mereka menolak untuk menyerah. Menggunakan kriteria keberdayaan masyarakat bawah yang dikemukakan Tjokrowinoto (1987) tersebut di atas, tampaknya para perempuan perajin batik gumelem sudah mulai berdaya. 6.KESIMPULAN Kendala-kendala yang dihadapi para perempuan perajin batik gumelem: 1. Tidak ada perjanjian kerja secara tertulis.Hubungan antara pekerja dengan juragan adalah kepercayaan karena tidak ada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. “Kesepakatan kerja” sepenuhnya ditentukan juragan.Kedudukan antara pekerja dan juragan tidak seimbang, dimana juragan dalam posisi dominan.. 2. Sistem pengupahan ditentukan secara sepihak oleh juragan. Perempuan perajin batik mempunyai bargaining power yang lemah terutama berkaitan dengan upah yang diperolehnya. 3. Tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Perempuan perajin batik pada umumnya tidak memiliki akses ke jaminan sosial dan tidak juga diberi tunjangan kesehatan oleh pengusaha/juragan,semua tergantung “kemurahan hati” juragan. 4. Keterbatasan akses terhadap bahan bakukarena malam (lilin) dan kain mori.Bahan baku ini belum tersedia di Banjarnegara dan harus dibeli di Banyumas, bahkan di Pekalongan. 5. Produktivitas kerja belum stabil. Pekerja menganggap bahwa pekerjaan membatik ini adalah pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama. 6. Maraknya batik cap/printing. Tempo waktu pengerjaan yang lama ditambah kegiatan membatik masih dianggap pekerjaan sambilan, membuat batik gumelem sulit memenuhi permintaan pasar baik dari sisi harga maupun ketersediaan barang sehingga membuat pengusaha berpaling ke batik cap. 7. Masuknya industri bulu mata palsu.Ketika perajin batik menganggap pekerjaan membatik tidak lagi menguntungkan, mereka beralih pekerjaan menjadi buruh 109 pembuatan rambut palsu dan bulu mata palsu (buruh ngidep) di perusahaanperusahaan rambut palsu yang menawarkan upah lebih tinggi. 8. Kurangnya regenerasi.Hanya sedikit kaum muda yang tertarik menjadi perajin batik tulis. 9. Rendahnya akses terhadap bantuan pemerintah.Pemkab Banjarnegara telah melakukan berbagai terobosan untuk nguri-uri batik gumelem dengan berbagai upaya,namun bantuan dan pemkab dan pemprov lebih banyak dinikmati para juraga. 10. Belum ada perkumpulan atau paguyuban perempuan perajin batik gumelem. Padahal dengan adanya paguyuban diharapkan dapat menyatukan para pembatik sehingga dapat meningkatkan bargaining power mereka di hadapan pengusaha/juragan.Selain itu, dengan adanya kelompok maka akan mempermudah para perajin dalam memperoleh bantuan pemerintah. Upaya yang dilakukan Para perempuan perajin bersepakat untuk membuat kelompok sebagai langkah awal membentuk koperasi, yakni Kelompok Giri Alam dari Desa Gumelem Wetan yang diketuai Mbak Wr dan Kelompok Pandan Sari dari Desa Gumelem Kulon yang diketuai oleh Mbak Ng. Kelompok Giri Alam fokus menggarap batik tulis dengan pewarna alami, sementara Kelompok Pandan Sari fokus menggarap batik tulis dengan motif gumelem. Dengan berkelompok mereka dapat lebih mandiri karena peluang untuk mengakses bahan baku murah dan pasar lebih terbuka. Demikian juga akses terhadap bantuan pemerintah yang selama ini “dibajak” para juragan. 6.DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan. 1997. “Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan ”dalam Sangkan Paran Gender, Irwan Abdullah ( e d . ) . Yogyakarta: PustakaPelajar. Ardhanariswari, Riris, Sofa Marwah , dan Tri Rini Widyastuti. 2014. Pengembangan Model Putting-out System untuk Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Perajin Batik Banjarnegara. Universitas Jenderal Soedirman: Penelitian Hibah Bersaing. Chotim, Erna Ernawati. 1994. Subkontrak dan Implikasinya terhadap Pekerja Perempuan: Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan. Seri Working Paper AKATIGA No.3. Bandung: Yayasan Akatiga. Fakih, Mansour. 1997.Analisis Gender dan Transformasi Sosial,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. alih bahasa Tri Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media. Hart, Keith. 1989. Informal Workers in Development. London: University Press. Mas’oed, Mochtar. 2006.Bahan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik. Kerjasama PSG UGM Yogyakarta danPPGAUnsoed Purwokerto. Miles, Matthew B. and A. Michel Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press. Newman, Lawrence. 1994. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon. Punch, Keith. 2006. Developing Effective Research Proposal. London: Sage Publication. Rochmawati, Dilli. 2010. Banyumas Membatik Makna (Analisis Semiotik Makna Sosial Budaya dalam Motif Batik Banyumasan). Skripsi, FISIP Unsoed, Purwokerto. 110 Safaria, A.F. 2003. “Sistem Maklun (Subkontrak) sebagai Startegi Buruh untuk Bertahan” dalam A.F. Safaria, dkk. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan Akatiga. Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1990. Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques. Beverly Hills: Sage Publications. Suratiyah, Ken. 1997. “Pengorbanan Wanita Pekerja Industri”dalam Sangkan Paran Gender, Irwan Abdullah (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syaifudian, Hetifah dan Erna Ernawati Chotim. 1994.Dimensi Starategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak pada Industri Garmen Batik. Akatiga: Bandung, 1994. Tjokrowinoto. Moeljarto.1987.Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah,dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana. http://www.batikgumelem.com/2013/03/mengenal-batik-gumelem-banjarnegara_21. html, diakses 7 Juli 2014 http: banjarnegarakab.go.id dan http://dokumentergumelem.blogspot.com/2009/12. Diakses 10 Juli 2014. www.antaranews.com/berita/531651/gubernur-jawa-tengah-tetapkan-umk-2016. Diakes 30 April 2016. 111 RELASI STRUKTUR DAN AKTOR DALAM ARENA KONTESTASI POLITIK PEREMPUAN17 1 Sulsalman Moita, 2I Ketut Suardika Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Halu Oleo Email: [email protected] 2 Jurusan Pendidikan Seni Budaya Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Email:[email protected] 1 Abstract This research was conducted in the city of Kendari Southeast Sulawesi, with the aim of:(1) analyze the strengths and political struggle actor (female) Emitter participate in the political arena; (2) describes the role of structural factors in the arena of political contestation women; and (3) review and analyze the consequences of relationship structures and actors in influencing gender relations in parliament.The research is a qualitative case study approach to examine the relationship of structure and actors in the arena of political contestation women. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data were then analyzed using qualitative data analysis, the analysis undertaken since the data collection until the research is completed.The results showed that: (1) The political struggle actor (female) in the arena of political contestation childbirth movement and the struggle against political structure mendominiasi and subordinating through internal strength and individual moral actor, meaning self encourage rationality of politics, the movement itself as a reflection of understanding in politics; (2) The role of structural factors pushing women's struggles to compete in the political arena which manifests itself in a number of institutions such as political institutions, the election organizers, media / press, women's NGO, the Centre for the Study of Gender and Women's Organization; (3) The consequences of the relationship structures and actors affecting gender relations in Parliament include: the allocation of resources, access, control, participation and benefit. Keywords: Relationships, Structures, Actors, Gender, Politics. 1.PENDAHULUAN Tampilnya sosok politisi perempuan baik dalam politik lokal maupun politik nasional di Indonesia, bukanlah fenomena yang unik. Seperti diutarakan oleh Manuell Castells (1997) dalam The Power of Identity bahwa transformasi politik dunia menjelang abad ke-21, salah satunya ditandai oleh fenomena runtuhnya tatanan patriarki di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, maka ranah politik yang selama ini dimaknai sebagai dunia laki-laki, mengalami transformasi besar-besaran yang tidak saja menempatkan hadirnya kaum perempuan namun juga tampilnya diskursus feminis dalam arena politik. Di Indonesia, kiprah perempuan di arena politik belum terlalu menggembirakan. Selama satu dasawarsa, yakni periode 1987 hingga 1997, keterwakilan perempuan hanya 12,06% (Irmayani & Osta F.P, 2009; Omara, 2009). Tonggak kebangkitan perempuan di arena politik diharapkan muncul, setelah hadirnya undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Partai Politik dan undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, untuk mencalonkan minimal 30% kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif. Secara sosiologis Undang-Undang tersebut telah mencerminkan realitas yang ada di masyarakat, yang berusaha mengakomodasi tuntunan masyarakat yang menghendaki adanya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. 17 Disajikan dalam rangka Konferensi Nasonal Sosiologi V, Padang 17-19 Mei 2016 112 Meskipun kedua undang-undang di atas, tidak sepenuhnya memberikan jaminan peningkatan partisipasi politik perempuan, namun setidaknya dapat menjadi starting point bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam politik di Indonesia. Selama dua Pemilu, keterwakilan perempuan di kursi legislatif mengalami peningkatan, yaitu 11,6% pada Pemilu 2004 dan 18% pada Pemilu 2009. Kendatipun secara nasional persentase keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30%, namun berbeda dengan Kota Kendari pada Pemilu 2009 dari 30 kuota kursi anggota legislatif, 10 orang (33%) adalah perempuan; kemudian pada Pemilu 2014 dari 35 kuota kursi 13 orang (37%) adalah perempuan. Kota Kendari juga merupakan satu-satunya dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menempatkan keterwakilan lebih 30% perempuan sebagai anggota legislatif. Konfigurasi keterwakilan perempuan di parlemen Kota Kendari merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologi gender dan sosiologi politik, karena tidak hanya semata-mata tercapainya persentase keterwakilan perempuan di parlemen; namun proses yang mengantarkan mengapa dan bagaimana kaum perempuan dapat eksis dan setara di arena politik, di tengah dominannya kaum laki-laki dengan kultur patriarkinya. Salah satunya adalah terjadinya rekonstruksi atas konstruksi sosial yang selama ini menganggap perempuan adalah subordinat laki-laki di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Rekonstruksi sosial merupakan salah satu kajian filsafat sosial yang menuntut diperlukan suatu teori kritis yang substantif mengenai masyarakat yang dikembangkan ke taraf metateoritis dalam kaitannya dengan upaya refleksi diri terhadap teori dan metode. Aliran ini juga bertujuan melakukan emansipasi sosial dan berusaha menemukan teori sosial yang mampu memikul tanggung jawab berupa perlawanan terhadap status quo. Asumsi utama yang dikedepankan adalah upaya kritik yang lebih luas terhadap kenyataan bahwa kultur kapitalis yang merupakan suatu bentuk manipulasi dan penguasaan, yang secara total meresapi struktur psikis dan sosial. Berkaitan dengan pemahaman rekonstruksi sosial, membawa pada kajian tentang relasi stuktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan. Perjuangan politik aktor (kaum perempuan), di samping dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri, juga didukung oleh faktor-faktor struktural seperti media massa, organisasi politik, dan organisasi semi politik. Masing-masing berusaha membangun suatu makna baru dalam keterwakilan perempuan dalam politik. Tentu saja melalui, perang wacana, ide, ideologi atas keterwakilan perempuan yang dapat diterima oleh masyarakat pemilih. Jika pada masyarakat telah terbentuk suatu konstruksi sosial tentang sesuatu, maka proses rekonstruksi bisa membentuk konstruksi sosial yang baru di antara komunitas tertentu yang melakukan resosialisasi. Relasi struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan, tidak hanya berhenti pada agenda perjuangan memenuhi keterwakilan 30% perempuan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Politik; akan tetapi relasi juga dilakukan ketika menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, budgetting, dan pengawasan. Selain itu politisi perempuan di parlemen, berada pada level yang sejajar dengan kaum pria, yang nampak dalam keseimbangan posisi jabatan pimpinan, fraksi, dan komisi. Fenomena eksistensi politisi perempuan di DPRD Kota Kendari, menunjukkan adanya konsekuensi pada pola relasi gender dalam bentuk alokasi sumber daya, akses, dan partisipasi yang dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; termasuk secara ekslusif politisi perempuan di wilayah ini telah membentuk kaukus perempuan parlemen sebagai satu-satunya kaukus yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang agendanya memperjuangkan pembangunan yang responsif gender dan anggaran yang pro gender. 113 Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini diharapkan dapat menjelaskan perspektif sosiologis dari relasi struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan di Kota Kednari. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakekuatan dan perjuangan politik aktor (kaum perempuan) dalam arena kontestasi politik di Kota Kendari?, Bagaimana peranan faktor-faktor struktural di arena kontestasi politik perempuan di Kota Kendari? dan Bagaimana konsekuensi relasi struktur dan aktor dalam mempengaruhi relasi gender di parlemenKota Kendari? 2.TINJAUAN PUSTAKA Secara umum terdapat dua model analisis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini dalam perspektif gender, yakni model analisi mikro dan meso. Model analisis mikro, menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Penjelasan berparadigma definisi sosial ini menganggap individu-individu anggota masyarakat bukannya ‘obyek’ (benda mati) yang siap ‘dibentuk’ dan selalu dijadikan sasaran kekuatan eksternal (struktur sosial dan budaya), melainkan individu-individu yang aktif, kreatif dan mempunyai kemampuan merespon stimulasi eksternal yang dinilai merugikan kepentingannya. Individu mempunyai kemampuan dan kapasitas yang memadai sehingga pada gilirannya mampu mereproduksi dan merekonstruksi sesuatu yang dinilai ‘given’ oleh masyarakat. Teori-teori yang dapat dipergunakan dalam model penjelasan mikro ini, misalnya Teori Fenomenologi dan Teori masyarakat aktif. Selanjutnya model analisis meso adalah kajian yang akan mensinergikan perdebatan dua kubu teoritisi besar yakni paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial. Paradigma inilah yang menurut Giddens menghasilkan teori strukturasi. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk yang bermakna hanya melalui kerangka struktur. Model analisis mikro dan meso di atas, kemudian disinergikan dengan pemikiran rekonstruksionisme. Pendekatan ini muncul karena terjadi kesenjangan dan kekecewaan terhadap teori-teori umum yang tidak dapat bersikap “kritis”. Rekonstruksionisme mendasarkan pada dua premis mayor: (1) masyarakat membutuhkan rekonstruksi yang konstan atau perubahan, dan (2) perubahan sosial juga adalah rekonstruksi pengetahuan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat. Pada intinya rekonstruksionisme bertujuan untuk mengkongkretisasi kehidupan, di mana dibentuk institusi sosial yang diawasi masyarakat, sekolah dan pendidikan dalam koordinasi sosial budaya dan arah yang harus sesuai keinginan masyarakat (Hamalik, 2007). Berdasarkan penjelasan konsep filsafat rekonstruksionisme, maka teori sosiologi yang relevan untuk mengkaji rekonstruksi kesetaraan gender dalam politik adalah: teori masyarakat aktif dari Etzioni. Model yang diperkenalkan Etzioni (dalam Poloma, 2007) untuk menjawab berbagai isu-isu sosial masyarakat modern termasuk gender, yaitu: 1) Bagaimana seseorang mengendalikan masa depannya?; 2) Bagaimana masa depan itu lebih banyak ditentukan tindakan rasional tetapi spontan; 3) Bagaiman aktor individual diarahkan?; 4) Sejauh mana kebenaran kekuatan self-kontrolnya? Lebih jauh Etzioni, mengungkapkan bahwa orientasi masyarakat aktif memiliki tiga komponen yakni: kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor, dan komitmen pada satu atau lebih tujuan. Teori Etzioni tersebut, jika disinergikan dengan eksistensi perempuan dalam politik, maka proses rekonstruksi, mengacu pada tiga komponen masyarakat aktif, yaitu: Pertama, perempuan perlu meningkatkan kesadaran pribadi yang tumbuh atas motivasi untuk berkiprah di dunia politik. Kedua, pengetahuan para aktor, yaitu perempuan memiliki pengetahuan dan 114 pengalaman politik untuk berkompetisi di arena politik yang umumnya dikuasai oleh kaum laki-laki. Ketiga, kaum perempuan berkomitmen pada satu atau lebih tujuan dalam berpolitik, seperti tujuan aktualisasi diri dan tujuan prestasi. Selanjutnya, relasi struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan juga dapat dikaji dari pendapat salah seorang teoritisi gender yakni Simone de Beauvoir. Menurut Beauvoir (1999), bahwa atribut seorang wanita bukan ada sejak dilahirkan melainkan diciptakan oleh lingkungan budayanya. la mengatakan bahwa eksistensi diri manusia bukan bawaan sejak lahir, melainkan merupakan pilihan, karena itu hak setiap individulah untuk menetapkan identitas dirinya. Filsafat eksistensialisme ini menjadi dasar pemikiran aktivis feminisme yang percaya bahwa identitas gender harus dikonstruksi oleh individu yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan identitas dirinya, maka seorang perempuan harus menjadi dirinya sendiri (otonom), dan lepas dari pengaruh alam. Kajian relasi struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan juga dapat dianalisis dalam perspektif gerakan sosial. Menurut Scoot (2011), di dalam gerakan sosial terdapat aspek-aspek mikro (dalam internal diri aktor) yang mempengaruhi gerakan yakni: ideologi diri, nilai-nilai diri, perspektif memandang suatu fenomena, sumber daya diri, dan komitmen diri. Gerakan internal diri aktor dapat mempengaruhi realitas perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Gerakan dalam internal diri, merupakan usaha untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan. Ini berarti gerakan perempuan harus menyusun strategi tentang bagaimana memberi warna perempuan pada setiap gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antar manusia yang beradab, termasuk dalam kehidupan politik. 3.METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berusaha memahami pemaknaan individu dari subjek yang ditelitinya. Peneliti melakukan interaksi dan komunikasi yang mendalam dan intensif dengan fihak yang diteliti, termasuk di dalamnya peneliti harus mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisa terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yakni penyelidikan intensif tentang individu, dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Lokus penelitian di DPRD Kota Kendari, dengan pertimbangan: 1) DPRD Kota Kendari merupakan satu-satunya DPRD Kabupaten/Kota di Sultra yang mampu menempatkan keterwakilan 30 % perempuan anggota legislatif; 2) keterwakilan perempuan sebagai anggota legilatif, tidak hanya semata-mata memenuhi keterwakilan 30% berdasarkan Undang-Udang Pemilu dan Undang-Undang Politik akan tetapi di dalamnya ada proses perjuangan dan gerakan yang mengantarkan tercapainya kuota tersebut serta konsekuensi relasi struktur dan aktor, baik dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif maupun implikasinya terhadap pola relasi gender dan responsif gender. Subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah subyek yang secara langsung melakukan proses perjuangan untuk kesetaraan gender, yakni 13 orang anggota DPRD Kota Kendari periode 2014-2019. Penelitian ini juga menggunakan informan pendukung, antara lain: pimpinan dan anggota DPRD; pimpinan dan pengurus parpol; pers (media massa); Stakeholder yang peduli terhadap program kesetaraan gender, seperti LSM perempuan Pusat Studi Gender, ormas perempuan; masyarakat (konstituen); dan penyelenggara Pemilu. Kriteria penentuan 115 informan pendukung di atas adalah mereka yang memahami secara mendalam dan akurat tentang masalah penelitian, serta jujur dan terbuka dalam memberikan data atau informasi. Berdasarkan sumbernya, data yang dipergunakan terbagi ke dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dan sejumlah informan pendukung. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subyek penelitian yang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan untuk mengetahui bagaimana perilaku sosial subyek yang diteliti berkaitan dengan tema-tema yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen yaitu data dari instansi/fihak terkait, seperti Sekretariat DPRD, Partai Politik pengusung, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa proses secara bertahap yaitu: 1. menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahaminya; 2. mereduksi data dengan cara abstraksi (menganalisis dan merangkum intisari data); 3. menyusun data dalam satuan atau klasifikasi; 4. satuan itu dikategorisasi sambil membuat koding; dan 5. memeriksa keabsahan data. 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN Pola Perjuangan Politik Aktor (Kaum Perempuan) dalam Arena Kontestasi Politik di Kota Kendari Dalam penelitian ini, kekuatan dan perjuangan aktor (perempuan) untuk setara merupakan landasan pencerahan dan pengetahuan untuk berjuang melawan kungkungan dominasi. Perjuangan untuk kesetaraan juga dimaknai sebagai suatu gerakan, aksi dan reaksi atas marginalisasi dan subordinasi kaum perempuan dalam politik. Esensi gerakan dan perjuangan untuk meningkatkan kapasitas politik kaum perempuan diilhami oleh paradigma teori-teori kritis dalam feminisme dan pembangunan, bersinergi oleh lahirnya kesadaran diri atas dasar pemaknaan (fenomenologi) yang berdialektika dengan kekuatan aktor di dalam struktur, sehingga menghasilkan dualitas struktur dan aktor (strukturasi). Hasil penelitian, menjelaskan bahwa moral individu (aktor) menjadi kekuatan utama terjadinya proses rekonstruksi kesetaraan gender dalam politik. Individu memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi untuk berjuang karena adanya faktor-faktor internal dalam diri, seperti jenjang pendidikan, latar belakang profesi, pengalaman organisasi, kepercayaan diri, motivasi, kesadaran diri, kapasitas bersaing, komitmen, dan sebagainya. Faktor-faktor internal tersebut bersinergi dan didukung oleh kekuatan eksternal seperti partai politik, pemilih, media massa, organisasi perempuan, dan stakeholder lainnya. Kondisi sosial budaya yang mempengaruhi proses kesetaraan gender dalam politik merupakan modal dasar yang diperlukan individu (aktor) untuk berjuang menjadi anggota DPRD. Kondisi inilah dimana mayoritas subyek penelitian sepakat bahwa dibutuhkan kapasitas diri sebelum mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota legislatif. Kapasitas yang harus dimiliki adalah input-input pribadi yang menjadi kekuatan awal, seperti tingkat pendidikan, latar belakang profesi, dan pengalaman organisasi. Signifikansi tingkat pendidikan subyek penelitian dalam mengaktualisasikan kiprah politik mereka untuk menjadi caleg, mempengaruhi struktur kognitif berupa: 1) pengetahuan dasar tentang politik, 2) pemahaman awal mengenai tugas dan kewajiban sebagai anggota legislatif, dan 3) tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk berkompetisi. Struktur kognitif tersebut melahirkan makna-makna dasar dalam diri sebagai landasan awal menguatnya harapan, motivasi, dan upaya untuk menjadi politisi. 116 Latar belakang profesi menjadi kekuatan pendorong bahwa terdapat nilai-nilai, moral, etika, dan etos yang dapat mengantarkan seseorang memiliki jati diri untuk eksis dan dikenal oleh orang lain sehingga tercipta relasi timbal balik dalam aktivitas politik. Ditinjau dari aspek pemaknaan diri sebagai bagian dari gerakan untuk setara, pengalaman profesi menjadi modal sosial sekaligus menjadi investasi sosial sehingga ketika dikonversi pada aktivitas-aktivitas politik akan menjadi modal politik. Pada aspek pengalaman organisasi menjadi kekuatan pendorong untuk mendobrak tradisi bahwa politik itu pada umumnya hanya identik kaum dengan laki-laki. Mereka menyadari bahwa tanpa pengenalan organisasi, kaum perempuan tidak bisa memahami kepemimpinan, kedisiplinan, komitmen, strategi, tanggungjawab, peran, dan sebagainya. Sehingga begitu pentingnya organisasi, semua subyek penelitian sepakat bahwa untuk menjadi politisi termasuk anggota DPRD mesti didukung oleh pengalaman organisasi. Selanjutnya pemaknaan diri sebagai kekuatan dan etos dalam proses perjuangan politik di arena kontestasi, memfokuskan pada lahirnya suatu sikap, tindakan, dan gerakan untuk setara melalui pemaknaan diri (aktor). Pemaknaan diri adalah proses bagaimana seseorang mengendalikan masa depannya dengan tindakan rasional serta kekuatan kontrol diri yang dimiliki. Untuk mengendalikan masa depan maka diperlukan proses belajar yang bersinergi dengan pengalaman-pengalaman. Upaya mengendalikan masa depan secara otonom melalui proses belajar adalah salah satu bagian dari proses menuju kesetaraan politik di arena kontestasi. Guna memaksimalkan potensi kaum perempuan dalam politik, diperlukan kesadaran diri yang kuat, terarah, sistemik sehingga simpul-simpul politik yang selama ini membelenggu mereka menjadi terbuka seiring dengan kondisi struktural yang memberi peluang baik dalam bentuk regulasi, kebijakan, program maupun aksi-aksi konkrit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran subyek penelitian merupakan kekuatan animo dalam berpolitik. Animo politik menjadi landasan bahwa aktivitas politik didominasi oleh upaya berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi dalam diri maupun potensi luar diri yang bersinergi atas animo diri. Sejumlah indikator yang menjadi dasar munculnya kesadaran untuk turut dalam Pemilihan Umum 2014, antara lain: adanya pengalaman politik, motivasi untuk setara, dan akses politik. Atas dasar tersebut pengalaman politik mendorong kesadaran diri untuk ikut berpolitik pada Pemilu 2014. Motivasi untuk setara menciptakan ambisi yang kuat, meningkatnya inisiatif dan kemampuan mengarahkan energi positif untuk menjadi anggota parlemen. Selanjutnya pemaknaan diri berkorelasi dengan pemahaman identitas diri subyek penelitian dalam merespon gerakan sebagai politisi parlemen. Salah satu aspek yang memberi pengaruh yang signifikan terhadap identitas diri seorang aktor untuk berjuang adalah gerakan diri. Gerakan diri adalah bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial mikro berpusat pada individu, mengandung muatan seperti ideologi diri, nilai-nilai diri, perspektif memandang fenomena, optimalisasi sumberdaya diri, dan komitmen diri. Kesemua input gerakan diri tersebut, diintegrasikan ke dalam suatu keyakinan kuat yang disadari, dipahami, dan perjuangkan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan ideologi diri subyek penelitian dari ideologi nature menjadi ideologi nurture. Ideologi nurture dalam persepektif gender tidak diartikan sebagai bentuk pembangkangan dalam kehidupan keluarga, tetapi merupakan bentuk respon sikap dan tindakan bahwa dalam diri ada prinsip-prinsip untuk maju, berhasil, dan harapan yang sama dengan kaum laki-laki di dunia politik. Berkaitan dengan nilai diri, subyek penelitian sepakat bahwa nilai diri tidak hanya sekedar menjadi potensi tetapi harus diaktualisasikan melalui pemberdayaan secara maksimal dengan melihat fokus dan hasil yang diharapkan. Seorang calon anggota legislatif harus mampu memahami tipologi pemilih, sehingga ketika melakukan sosialisasi 117 politik akan terjalin interaksi dan komunikasi politik yang diharapkan. Nilai diri dapat integrasikan dengan harapan pemilih seperti kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat ketika terpilih sebagai anggota parlemen. Analisis selanjutnya mengenai gerakan diri adalah perspektif dalam memandang fenomena berdasarkan pengalaman-pengalaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, seluruh subyek penelitian sepakat bahwa sebelum perempuan terjun ke dunia politik maka harus tertanam dalam dirinya kultur politik. Kultur politik tidak hanya dilandasi oleh semangat bersaing belaka; akan tetapi dibarengi dengan performance guna merepresentasi politik perempuan di parlemen. Representasi politik perempuan di parlemen pada dasarnya telah dimulai ketika mencalonkan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ia sensitivitas gender ketika melakukan sosialisasi, silaturahmi, kampanye terbatas, maupun kampanye terbuka. Sinergi dengan optimalisasi sumber daya diri, para subyek penelitian sepakat bahwa potensi tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, dan pengalaman pekerjaan perlu dimaksimalisasi agar masyarakat dapat mengetahui kemampuan figur calon anggota legislatif.Pentingnya sumber daya diri oleh subyek penelitian sangat disadari, karena tanpa itu mereka tidak memiliki referensi yang cukup untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas bersaing. Terakhir adalah komitmen yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesutu. Sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014, merupakan langkah awal tumbuhnya komitmen tersebut. Para subyek penelitian menyadari bahwa pilihan sebagai calon anggota legislatif bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan partai politik pengusung; akan tetapi ada nilai tanggungjawab yang terpatri dalam diri subyek untuk memperjuangkan panji-panji partai politik pengusung yang berkaitan dengan ideologi, visi dan misi, dan program partai. Guna mewujudkan komitmen diri, para subyek penelitian melakukan strategi politik mulai dari strategi komunikasi politik, membentuk tim sukses, menyiapkan infrastruktur, strategi membangun opini publik, penggunaan media, dukungan kolega dan kelembagaan, dan sebagainya. Namun di antara komitmen dan tanggung jawab tersebut, setiap individu memiliki strategi yang khas yang menjadi kekuatan dalam upaya menanamkan kepercayaan dan ekspektasi publik. Selanjutnya perjuangan subyek penelitian, bersinergi dengan eksistensi struktur sosial dan politik sebagai medan dimana individu merefleksikan perilaku politiknya. Posisi struktur tidak membatasi individu untuk melakukan aktivitas politik, namun justru memberi peluang untuk melakukan perubahan yang didasari refleksi kesadaran diri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada 3 bentuk perjuangan yang dilakukan subyek penelitian pada Pemilu 2014 yaitu: tahapan pendaftaran atau pencalonan, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan suara. Tahap pencalonan adalah tahap pendaftaran sebagai caleg dengan melengkapi semua prosedur dan syarat administrasi berdasarkan regulasi yang ada. Tahap kampanye yakni subyek penelitian melakukan upaya-upaya konkrit guna mendapatkan simpati pemilih melalui kampanye dialogis, kampanye bermedia, dan kampanye terbuka. Tahap pemungutan suara adalah tahap yang paling menentukan dari seluruh tahapan pemilu karena disinilah kapasitas subyek diuji, apakah ia dipercaya oleh konstituen di Daerah pemilihanya untuk menjadi wakil rakyat. Peranan Faktor-Faktor Struktural dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan di Kota Kendari Teori strukturasi membawa kita pada pemahaman dan entitas kesadaran bahwa kehidupan manusia pada dasarnya berada pada dua elemen yang saling melengkapi, yakni elemen individu (aktor) dan elemen struktur (sistem sosial). Kedua elemen tersebut tidak saling meniadakan akan tetapi membangun aliansi sehingga tokoh sosiologi Anthony Giddens menyebutnya sebagai dualisme. 118 Kajian sinergi antara struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan, paling tidak dapat dijelaskan dalam analisis dualitas Giddens. Struktur menjadi akses bagi aktor untuk memperkuat peluang dan kapasitas berpolitik sementara aktor merupakan sosok dengan identitas dan kemandiriannya dapat mengontrol berbagai regulasi, program, dan kebijakan politik. Penelitian tentang rekonstruksi kesetaraan gender dalam politik menegaskan bahwa posisi aktor (subyek penelitian), tidak terpisahkan dengan posisi struktur. Kedua entitas tersebut saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling bersinergi sehingga cita-cita dan harapan tampilnya kaum perempuan di panggung politik dapat tercapai. Temuan penelitian mengungkapkan kondisi-kondisi struktural yang turut mempengaruhi proses kesetaraan gender dalam politik yakni bentuk perjuangan, aksi, komitmen, dan sinergi untuk menciptakan keadaan dimana kaum perempuan dapat mengambil peran dan peluang sebagai calon anggota legislatif. insitusi atau lembaga yang turut mempengaruhi secara signifikan upaya menuju kesetaraan; baik insitusi yang berkaitan langsung dengan proses-proses politik seperti Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik maupun institusi-instituusi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab mendorong perjuangan affirmative action, seperti organisasi Perempuan, Pusat Studi Wanita, Organisasi Keagamaan, dan media. Peranan yang pertama adalah institusi penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 tiga peran KPU yang signifikan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen yaitu: sosialisasi keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan caleg, sosialisasi keterwakilan melalui media, dan sosialisasi politik untuk pemilih pemula. Ketiga pola sosialisasi ini gencar dan efektif dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Kendari dalam merealisasikan keterwakilan perempuan di DPRD. Institusi politik lainnya yang signifikan dalam mendorong proses kesetaraan gender di parlemen adalah partai politik. Temuan penelitian menunjukan bahwa parpolparpol peraih kursi di DPRD Kota Kendari melakukan empat peran, yakni: kaderisasi dalam kepengurusan parpol, pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif, strategi dan kebijakan parpol terhadap caleg perempuan, dan peran parpol dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas anggota legislatif perempuan di parlemen. Khusus untuk strategi terhadap caleg perempuan, pada umumnya parpol menaruh atensi yang cukup penting dengan intens melakukan sosialisasi caleg baik melalui media maupun secara langsung dimasyarakat. Selain itu parpol juga umumnya memberikan pembekalan kepala caleg perempuan mengenai strategi bersaing, komunikasi politik, dan strategi memenangkan pemilu dengan mengemas isu-isu sensivitas gender. Selanjutnya, elemen struktur yang cukup signifikan sebagai wahana sosialisasi dan pendidikan politik adalah media. Eksistensi media, tidak hanya memberi informasi dan mempublikasi kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi namun media juga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Secara spesifik, media dapat menjadi wahana marketing politik bagi lembaga-lembaga politik, seperti parpol untuk mensosialisasikan visi dan misi, ideologi perjuangan, platform, dan kebijakan; termasuk memperkenalkan figur dan kandidat politisi perempuan yang akan berkompetisi memperebutkan kursi parlemen. Temuan penelitian menunjukan ada 3 indikator yang digunakan media guna mempengaruhi proses kesetaraan gender dalam politik, yakni : a. sosialisasi melalui siaran atau berita; b. sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat; dan c. sosialisasi melalui program atau rubrik khusus. Berkaitan dengan peranan stakeholder perempuan, menunjukkan bahwa terdapat institusi stakeholder perempuan yang turut memberi kontribusi terhadap upaya-upaya kesetaraan gender dalam politik, yakni: organisasi perempuan yang terdiri dari Koalisi 119 Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Perempuan (Alpen), dan Solidaritas Perempuan (SP); Pusat Studi Gender Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah; serta Ormas Perempuan masing-masing Aisiyah dan Muslimat NU. Organisasi perempuan merupakan stakeholder yang paling konsisten, reaktif, dan terstruktur dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik. Jaringannya, tidak hanya berbasis lokal dan nasional; akan tetapi terintegrasi dengan jaringan internasional. Berbagai langkah, upaya, dan strategi insiatif organisasi perempuan telah dilakukan mulai dari respon dan reaksi atas regulasi atau undang-undang yang mengatur keterwakilan, hingga melakukan pendidikan politik, pendampingan, proteksi, pembekalan, sosialisasi. Bahkan termasuk melakukan aksi-aksi sporadis lapangan untuk mengunggah kesadaran masyarakat akan pentingnya kemitraan dalam relasi antar laki-laki dan perempuan di ranah politik. Temuan penelitian mengelaborasi 3 (tiga) bentuk gerakan LSM Perempuan guna mendorong kesetaraan gender pada Pemilu 2009 dan 2014, yakni: a. rekomendasi dan sosialisasi; b. aksi-aksi lapangan; serta c. pembekalan dan pendampingan politik. Komponen stakeholder lainnya yang turut memberi kontribusi upaya-upaya mendorong kesetaraan gender dalam politik adalah Pusat Studi Gender Universitas Halu Oleo dan Universitas Muhammadiyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua pusat studi tersebut, sepakat dan berkomitmen untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik terutama keterwakilan di parlemen melalu riset, kajian, forum-forum diskusi, talkshow. Pusat Studi gender juga dapat membangun sinergi dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan perempuan pacsa terpilih melalui agenda proteksi, pendampingan, dan memaksimalkan potensi kaukus perempuan parlemen dalam memperjuangkan agenda-agenda pembangunan yang pro gender. Selanjutnya organisasi keagamaan yang berkontribusi dalam upaya mendorong kesetaraan gender adalah organisasi Aisyiah Sultra dan Muslimat NU. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, DPW Aisyiah Sulawesi Tenggara memiliki program pendidikan politik kaum perempuan. Program ini tidak secara empiris mendorong kader untuk berafiliasi pada partai tertentu atau mendukung kadernya untuk menjadi politisi. Akan tetapi pendidikan politik lebih diarahkan untuk memberikan pencerahan bahwa perlunya kaum perempuan lebih cerdas memilih partai politik yang sesuai dengan perjuangan organisasi. Selain itu memilih pemimpin yang amanah, peduli, dan merakyat sesuai dengan prinsip-prinsip pemimpin dalam ajaran agama. Organisasi Aisyiyah juga mendorong dan mendukung pengurus dan kader yang ingin berpartai atau menjadi caleg untuk menggunakan cara-cara politik yang santun, beradab, dan berfihak kepada perjuangan dan kepentingan masyarakat. Kemudian muslimat NU dalam mendukung keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2009 dan 2014 adalah: 1) pembenahan kualitas kader yang berminat untuk berkiprah sebagai politisi melalui motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas; 2) mendorong kader yang disamping dikenal oleh masyarakat juga mampu mengetahui masalah-masalah kemasyarakatan serta ketika terpilih dapat menjalankan tugas dan fungsi DPRD dan mampu bermitra dengan pemerintah guna memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ; 3) melakukan konsolidasi kepengurusan mulai dari tingkat atas sampai tingkat cabang, dan ranting guna mendukung kader yang menjadi caleg pada pemilu legislatif. Konsekuensi Relasi Struktur dan Aktor dalam Mempengaruhi Relasi Gender di Parlemen Kota Kendari Upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam politik dalam konteks relasi struktur dan aktor, tidak hanya pada terpenuhinya persentase keterwakilan perempuan di parlemen, namun apakah keterwakilan tersebut berkorelasi pelaksanaan 120 tugas dan fungsi parlemen. Secara empirik ada dua hal yang menjadi fokus, yakni konsekuensi terhadap relasi gender dan responsif gender. Konsekuensi terhadap relasi gender adalah posisi kaum perempuan sebagai subyek yang pro aktif terhadap penjabaran tugas pokok dan kewenangan legislatif. Perempuan sebagai wakil rakyat dapat membuktikan kapasitas, kompetensi, dan potensinya untuk sejajar, mendesain dan memaksimalisasi fungsi-fungsi parlemen serta mengemban aspirasi masyarakat. Sedangkan konsekuensi terhadap responsif gender adalah upaya-upaya merespon program, kebijakan, dan anggaran yang pro gender baik atas dasar inisiatif dan perjuangan perempuan legislatif maupun atas dasar komitmen bersama anggota parlemen. Indikator kebijakan yang pro gender termanifestasikan pada sejauhmana program-program gender yang melekat di setiap lembaga pemerintahan telah mencerminkan rasa keadilan? Apakah pengambil kebijakan menaruh perhatian yang memadai terhadap kepentingan kaum perempuan? Sedangkan indikator anggaran yang pro gender adalah sejauhmana alokasi anggaran telah memenuhi kuantitas dan kualitas yang diharapkan publik, dan apakah anggaran tersebut mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya? Selanjutnya konsekuensi responsif gender lainnya adalah terbentuknya kaukus perempuan parlemen, yang tidak hanya bermakna mengorganisir kekuatan anggota legislatif perempuan sebagai simbol kesetaraan namun dapat menjadi wadah perjuangan mendorong dan meningkatkan program dan anggaran yang pro gender. Berkaitan dengan relasi gender, temuan penelitian menunjukkan bahwa lima bentuk relasi yang mampu dilakukan oleh perempuan parlemen Kota Kendari, yakni: a. Alokasi sumber daya, yang nampak pada keseimbangan pada jabatan pada alat kelengkapan parlemen, kedudukan dalam panitia khusus, dan jabatan dalam Fraksi; b. Akses, nampak pada keseimbangan dalam proses lobi-lobi pembahasan anggaran dan melakukan penjaringan aspirasi; c. partisipasi. yakni perempuan parlemen cukup aktif dalam partisipasi sidang-sidang parlemen, hearing, dan dalam menerima aspirasi; d. kontrol, kemampuan anggota parlemen perempuan dalam mengontrol berbagai program dan keputusan eksektufi dan melakukan konsultasi dan koordinasi; serta e. manfaat yang diperoleh melalui peningkatan kapasitas dan penguatan relasi dengan konstituen. Selanjutnya berkaitan dengan responsife gender, temuan penelitian menunjukkan bahwa: eksistensi rekan-rekan anggota legislatif perempuan cukup pro aktif memperjuangkan anggaran dan program yang pro perempuan pada setiap pembahasan anggaran, baik di Komisi, badan anggaran, rapat pleno maupun rapat paripurna. Kaum perempuan sangat bersemangat, ngotot, dan kompak agar usul mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan terakomodasi. Selanjutnya, upaya untuk mendorong program dan anggaran yang responsife gender telah dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pasca terpilih, hal ini dapat dilihat pada alokasi anggaran dan sejumlah program ekslusive gender yang telah diperjuangkan. Namun semangat itu perlu dimaksimalisasi melalui penguatan kelembagaan melalui kaukus perempuan parlemen. 5.KESIMPULAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi struktur dan aktor dalam arena kontestasi politik perempuan merupakan gerakan dan perjuangan perempuan melawan stuktur politik yang mendominasi dan mensubordinasi. Pertama, diawali dengan kekuatan internal diri dan moral individu melalui kondisi sosial budaya yang mempengaruhi proses kesetaraan dalam politik yakni: latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, dan pengalaman organisasi. Kedua, (1) Pemaknaan diri individu memotivasinya bertindak 121 secara rasional dan menciptakan kesadaran diri untuk berpolitik. Kesadaran diri dalam berpolitik dipengaruhi oleh pengalaman politik, motivasi untuk setara dan akses politik; (2) Pemahaman diri subyek sebagai politisi melahirkan gerakan diri untuk kesetaraan yang terdiri dari: ideologi diri nurture, nilai diri sebagai pengabdian, budaya politik untuk bersaing, optimalisasi sumber daya diri, dan komitmen diri. (3) Upaya dan perjuangan subyek bersaing dalam Pemiu 2014 merupakan momentum untuk mengakualisasikan refleksi kesadaran dalam bentuk tindakan politik seperti: tahap pencalonan, tahap kampanye, dan tahap pemungutan suara. Peranan faktor-faktor stuktural dalam arena kontestasi politik perempuan, antara lain: Pertama, peranan KPU melalui: sosialisasi keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan dan melalui media, serta pendidikan politik untuk pemilih pemula. Peranan parpol melalui kaderisasi dalam kepengurusan, pencalonan perempuan sebagai kandidat, strategi dan kebijakan parpol terhadap caleg perempuan melalui sosialisasi dan pembekalan, serta peran parpol dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas anggota legislatif perempuan. Kedua, Peranan media dalam kesetaraan gender dalam politik melalui sosialisasi dalam siaran atau berita, sosialisasi iklan layanan masyarakat, dan sosialisasi melalui program khusus. Ketiga, Peranan stakeholder perempuan dalam proses kesetaraan gender dalam politik (1) organisasi perempuan melalui rekomendasi dan sosialisasi, aksiaksi lapangan, pendidikan dan pendampingan politik; (2) Pusat Studi Gender melalui penelitian, pengkajian, pemberdayaan, pendampingan, dan forum diskusi/seminar (3) Organisasi keagamaan melalui program pendidikan politik untuk perempuan, mendorong dan memotivasi kader potensial untuk berkiprah di dunia politik, melakukan advokasi pengarusutamaan gender, dan terlibat dalam forum-forum diskusi/seminar. Sinergi kesadaran diri subyek dan dukungan elemen-elemen struktural berpengaruh terhadap konsekuensi terhadap relasi gender dan responsif gender. Pertama, konsekuensi terhadap relasi gender mengejawatahkan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, melalui lima bentuk relasi yakni: konsekuensi alokasi sumber daya dengan indikator kesetaraan pada posisi atau jabatan, kedudukan dalam pansus, dan jabatan dalam fraksi; konsekuensi relasi terhadap akses yakni kemampuan subyek dalam proses akomodasi anggaran dan reses menindaklanjuti aspirasi masyarakat; konsekuensi relasi terhadap partisipasi, nampak pada keseimbangan partispiasi subyek dalam rapatrapat DPRD, rapat dengar pendapat, dan dalam menerima aspirasi; konsekuensi relasi terhadap kontrol melalui kemampuan dalam mengontrol kebijakan eksekutif, knosultasi, dan koordinasi; koneskuensi relasi terhadap manfaat yakni terjadinya peningkatan kapasitas dan penguatan relasi subyek penelitian dengan konstituen. 6.DAFTAR PUSTAKA Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies : A Theory of Gendered Organizations. London: Macmillan Press. Adian, Donny Gahral. 2010. Pengantar Fenomenologi. Depok : Koekoesan. Antrobus, Peggy. 2004. The Global women Movement. Bangladesh: The University Press. Astuti, Tri Mathaeni Puji. 2012. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. Semarang: Unnes Press. Beauvior, Simone De. 1999. Second Sex : Kehidupan Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Promothea. Berger, Peter L. & Luckmann Thomas. 1996. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. (Terjemahan). Jakarta: LP3ES. Bogdan dan Biklen. 1982. Qualitative Research for Education. Massacusette: Mc GrawHill Inc. Castells, Manuell. 1997. The Power of Identity. London and New York: Blackwell Publishing. 122 Dahlerup, Drude. 2006. Women Quotas and Politics. New York: Routledge. Fakih, Mansyour. 2002. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Giddens, Anthony. 2011. Teori Strukturasi : Dasar-Dasar Pembentukan Masyarakat. (Terjemahan Maufur & Daryatno). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hamalik, Oemar. 2007. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hermson, Paul S dan Lay, J Celeste, dan Stokes, Atiya.” Women Running “as women”: Candidate Gender, Campaign Issues, and Voter-Targeting Strategies”. The Journal of Politics, Vol.65, No.1,Februari 2003. Hobson, Barbara. 2003. Recognition Struggles And Social Movements; Contested, Identities, Agency And. Hutchings, Kimberly. 2010. Simone D Beauvior (dalam Teori-Teori Kritis, Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional). Terjemahan: Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Baca. Illich, I, 1983. Gender. London: Marison Boyars. Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Terjemahan : Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian). Bandung: Widya Padjadjaran. Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Kolonial. Jakarta : Rajawali Pers. Moser, C.O.N. 1993. Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. London: Roudledge. Ozmon, Howard A dan Samuel M Craver. 1990. Philosophical foundations of education. Melbourne: Merrill Publishing Company. Poloma, M. Margareth, Sosiologi Kontemporer, 2007. Yogyakarta : Penerbit Yayasan Solidaritas Gadjah Mada. Putri, Alfadioni, Utami Putri & Himam Fathul. Ibu dan Karir: Kajian Fenomenologi terhadap Dual-Career Familiy (Mother and Career: Phenomenological Approach on the Dual-Career Family). Jurnal Psikologi, Volume 32, Nomor. 1,Tahun 2007. Ridjal, Fauzie dkk (editor). 1993. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya. Ritzer, George & Smart Barry. 2011. Handbook Teori Sosial. Bandung: Nusamedia. Robinson, Cactherine dan Bessell. 2002. Women in Indonesia. Singapore: ISEAS. Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Sosial. Yogyakarta : PT Tiara Wacana. Santoso, Widjajanti, M. 2011. Sosiologi Feminisme, Konstruksi Perempuan dalam Industri Media. Yogyakarta: LKiS. Schrijvers, Joke. 1986. Mothers for Life. USA: Eburon Delft. Scoot, John. 2011. Sosiologi The Key Koncept. Jakarta : PT. Rajagrafindo Perkasa. Stanley, L. 1990. Feminist Praxis: Research, Teory and Epistimology in Feminist Sociology. London: Routledge. Susiana, Sali. Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD, dan DPRD. Jurnal Kajian, Volume 14, No 3, September 2008. 123 124 PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PEREMPUAN DESA 1 Vina Salviana Darvina Soedarwo 1Hutri Agustino 1 Jurusan Sosiologi, FISIP Email: [email protected] 2 Universitas Muhammadiyah Malang Email: [email protected] Abstract Majority of Indonesian women tend to be the object of politics, rather than being the subject of politics. A similar phenomenon was also experienced by rural women there are more involved in economic activities. One interesting phenomenon is the concern NGOs to conduct political education while also maintaining local economic development as part of community empowerment movement nuanced political awareness for women.Two women school in Batu City are interesting to examine that NGOs are Sekolah Perempuan Desa (SPD) as a pure manifestation of the people's aspirations and Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) was formed by government. This research uses a qualitative approach. The subject is the educators and women as the students, while the data collection techniques are in-depth interviews, observation, documentary and Focus Group Discussion. These research findings indicate that the SPD and PNFP able to provide political education with sufficient material for village women also some training that can develops their knowledge. One thing that is different from these two organizations are independently in funding the organization. SPD organization more independent than PNFP because PNFP is formed by the government, so PNFP has inadequate funds. Managerial and recruitment model of students in these two organizations are also a bit different as well as a model of economic development based on local potential. Keywords : Political Education , Local Economic Development, Rural Women 1. PENDAHULUAN Pemahaman yang keliru tentang konsep politik merupakan salah satu sebab kurangnya partisipasi politik oleh kaum perempuan.Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan dalam bidang politik masih relatif lemah.Perempuan-perempuan Indonesia mayoritas masih cenderung menjadi obyek politik, daripada menjadi subyek politik.Fenomena serupa dialami pula oleh perempuan desa, apalagi perempuan desa lebih banyak terkonsentrasi pada kegiatan yang lebih bersifat ekonomi.perempuan desa seringkali bekerja lebih lama dibandingkan lelaki, sebab mereka juga harus menjadi perawat yang mengurus anak, orang tua dan orang yang sakit. Selain itu, banyak dari mereka adalah penanam modal dan pengusaha kecil yang mendedikasikan sebagian besar penghasilan mereka pada kesejahteraan masyarakat dan keluarga mereka. Namun kebanyakan anak perempuan dan perempuan desa masih menghadapi rintangan lebih besar ketimbang lelaki dalam memperoleh akses ke layanan masyarakat, perlindungan sosial, peluang kerja yang merosot, dan pasar serta lembaga lain. Satu fenomena menarik adalah kepedulian Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan pendidikan politik sekaligus melakukan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini terjadi di kota Batu, sebuah kota wisata di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan lebih baik lagi. Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah Sekolah Perempuan Desa (SPD) yang murni perwujudan dari aspirasi masyarakat dan Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) di kota Batu. 125 Berpijak dari realitas itu, maka penelitian tentang pemberdayaan perempuan yang sarat dengan ideologi gerakan kesetaraan gender melalui pendidikan politik dan pengembangan ekonomi lokal ini menjadi sangat penting. Hal ini akan mendeskripsikan secara detail bagaimana potret keberdayaan politik dan ekonomi perempuan di tingkat lokal, khususnya pada era otonomi daerah yang menjadi bagian dari agenda keberlanjutan reformasi politik tahun 1998. Artinya, apakah memang era otonomi daerah mampu memberikan kepastian akan hak politik dan ekonomi perempuan di tingkat lokal atau justru dengan sistem tersebut peran dan fungsi perempuan makin tersubordinasi di wilayah periferial secara sosial, politik, budaya dan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, peran dan fungsi perempuan yang dimaksud adalah di wilayah Kota Batu khususnya yang menjadi siswa atau peserta didik di Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuidan mendeskripsikan pemberdayaan perempuan yang bernuansa gerakan kesetaraan gender melalui pendidikan politik dan pengembangan ekonomi lokal di dua sekolah perempuan desa yang satu sekolah didirikan oleh Lembaga Swadaya masyarakat dan di Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan satu sekolah lagi didirikan oleh pemerintah yang diberi nama dengan Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) milik Pemerintah Kota Batu. 2. TINJAUAN PUSTAKA Pemberdayaan masyarakat seringkali dikaitkan dengan perbaikan pendapatan atau income generating, namun hal ini belum cukup karena perlu adanya dorongan masyarakat untuk mandiri demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan dalam pelbagai aspek. Mardikanto dan Purwaka menegarai bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait peningkatan pendapatan tetapi diperlukan advokasi hokum/kebijakan bahkan pendidikan politik yang memadai sehingga dapat memperkuat daya tawar politis18.Dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pendidikan politik yang dimaksud adalah bagaimana menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam menyuarakan hak-hak politik masyarakat bukan masyarakat sebagai kendaraan politik. Demikian pula perempuan sebagai bagian dari masyarakat perlu mendapat perhatian tersendiri berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah menumbuhkan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan mampu menyuarakan hak-hak politik mereka untuk kepentingan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada saat ini harus diakui meskipun partisipasi perempuan telah dibuka lebar, tetapi masih ada ketidakberdayaan (empowering) perempuan khususnya dalam bidang politik.Hal ini terkait erat dengan kedudukan perempuan dalam masyarakat tradisional, dimana perempuan ditempatkan untuk mengelola urusan-urusan keluarga, atau sebagai pekerja untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Dengan demikian perempuan bukan penentu keputusan untuk menghasilkan sesuatu, dengan kata lain perempuan bukan sebagai subyek tetapi hanya sekedar sebagai obyek atau pelaksana. Melihat kenyataan yang didasarkan teori dan pendapat dari para pakar, maka sangat penting adanya upaya-upaya untuk memberdayakan perempuan dalam bidang politik agar kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam dimensi politik pemberdayaan menyangkut proses peningkatan kesadaran perempuan akan kemampuan mereka, akan hak dan kewajibannya, dan mampu menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk mengorganisasikan diri mereka sendiri artinya mereka berdaya secara politik. 18 Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfaabeta. Hal. 161. 126 Temuan Harnoko menyimpulkan bahwa untuk membangun keberdayaan politik perempuan maka ada tiga ikhwal yang mendasar yaitu hak, aspirasi dan akses. Kesadaran akan hak danurgensi perempuan berperan di bidang politik adalah menjadi ikhwal utama yang harus dibangun. Pendidikan politik bagi perempuan yang dilakukan baik olehmasyarakat maupun pemerintah dan juga partai politik sangat penting tapi justru bagian inilah yang sering terabaikan. Pola pikir lembaga pemberdayaan dan institusi politik masih terkesan diwarnai paradigma lama dengan budaya tradisional, serta masih mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan.19 Fenomena langkanya pendidkan politik bagi perempuan dibuktikan pula oleh hasil penelitian Salviana, dkk (2004) tentang “Pengembangan Model Pendidikan Politik Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Parpol dan Ormas Organisasi Perempuan” menunjukkan bahwa belum ada pendidikan politik yang memadai bagi kader perempuan pada partai politik dan ormas yang lebih periodik dan terfokus apalagi berbasis pendidikan politik kesetaraan gender. Dari hasil penelitian tersebut dapat disatrikan bahwa pendidikan politik masih minim baik untuk kader parpol maupun di luar parpol, sehingga upaya Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan pendidikan atau transfer pengetahuan tentang politik menjadi sangat kontributif bagi pengembangan wawasan politik bagi warga masyarakat khususnya perempuan.20Dikotomi antara laki-laki dan perempuan memang tercermin dari pandangan umum bahwa laki-laki lebih pantas berkiprah di bidang politik dari pada perempuan, hal ini didukung pula oleh minat perempuan dalam berpolitik yang cenderung menyukai politik di tingkat lokal daripada di tingkat nasional.Seperti yang dinyatakan Rai, dkk bahwa perempuan lebih nyaman berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal dari pada yang jauh dari tempat tinggalnya.21 Di beberapa negara dunia ketigapun pendidikan politik sudah mulai dikaji secara ilmiah seperti hasil riset Ni Ketut Restini, dkk (2014) menunjukkan bahwa dari segi pendidikan politik bagi kaum wanita di desa Tigawasa Kabupaten Buleleng, Bali lebih banyak berlangsung secara informal, artinya pendidikan politik bagi perempuan di desa tersebut dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sehari-hari dimasyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari sebagian besar kaum perempuan desa pendidikannya hanya sampai di tingkat sekolah dasar. Proses pendidikan politik perempuan di desa ini berakar pada kebudayaan masyarakat di desa itu sendiri. Pendidikan politik di desa ini diwarnaidan dijiwai oleh nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat itu sendiri. Pemahaman dan orientasi politik perempuan desa ini terbentuk secara alamiah22. Dari berbagai temuan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan baik yang berupa pendidikan politik ataupun peningkatan pendapatan di negara dunia ketiga perlu perhatian penuh mengingat masih rendahnya perempuan dalam keterlibatannya pada berbagai aspek. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Kabeer (2001)23 bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut. (1) Welfare (Kesejahteraan): aspek ini Bambang Rudi Harnoko, 2012.“Pendidikan Politik Perempuan Dalam Konteks Negara Demokrasi” dalam MUWÂZÂH, Vol. 4, No. 2, Desember. 20 Salviana, dkk 2004. Pengembangan Model Pendidikan Politik Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Parpol dan Ormas Organisasi Perempuan,PHB-DIKTI. 21 Shirin M Rai. Farsana Bari, Nazmunessa Mahtab dan Bidyut Mohanty. 2005.“Gender Quotas and The Politics of Empowerment-A Comparative Study” dalam Woman, Quotas and Politics, edited by Drude Dahlerup. London: Routledge. Hal. 222. 22 Ni Ketut Restini, dkk. 2014. Pendidikan Politik Berbasis Desa Adat Bagi Kaum Perempuan Di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Bulelen. ejournal.undiksha.ac.id (diakses 30 Maret 2016 ). 23 Naila Kabeer. . 2001. Reflections on The Measurement of Women’s Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices. Sida Studies No3 . LSE Research Online.Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm, Sweden, pp. 17-57. 19 127 dapat dikatakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan.Terutama berkaitan dengan partisipasi ekonomi. (2). Access (akses) :akses terhadap teknologi dan adalah penting mengingat melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka. 3. Consientisation (konsientisasi): pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. 4. Participation (partisipasi) yaitu ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan.Equality of Control (kesetaraan dalam control kekuasaan): kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang setara. Sekolah perempuan di desa rupanya menjadi alternatif bagi pemberdayaan perempuan di tingkat lokal agar perempuan diupayakan kesejahteraannya meningkat, akses teknologi untuk kebutuhan ekonomi dan sosial mereka, pemahaman kesetaraan gender yang lebih meningkat, partisipasi yang meningkat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kesetaraan dalam control atau kekuasaan baik dalam produksi maupun distrib. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan prinsip nonprobability sampling.Misalnya, subjek tertentu dianggap paling mengetahui dan memiliki otoritas untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini atau bisa diistilahkan sebagai tokoh kunci (key persons)—baik dalam Sekolah Perempuan Desa (SPD) maupun di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu dalam hal ini adalah para pengurus atau pengelola kedua lembaga tersebut di samping itu juga para peserta didik dan para alumni. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang lazim digunakan menurut Denzin dan Lincoln24 adalah sebagai berikut: (a) Observasi terstrukturPeneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam pertemuan pelatihan, penyuluhan, simulasi atau bahkan pada saat subjek penelitian melakukan aksi dalam proses membangun gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di Sekolah Perempuan Desa (SPD) maupun di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu dengan concern pengembangan ekonomi lokal.(b) Wawancara Mendalam: Penggunaan teknik ini ditujukan untuk keperluan koleksi data strategi gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di Sekolah Perempuan Desa (SPD) serta pengembangan ekonomi lokal di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota BatuTantangan dan dinamika yang dihadapi saat membangun gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan pengembangan ekonomi lokal di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu. (c) Dokumenter: Penelitian ini tentu juga membutuhkan justifikasi data sekunder berupa dokumentasi foto, video, artikel dan kliping berita yang relevan dengan tema penelitian—baik itu akan diperoleh dari Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang 24 Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009.Handbook of Qualitative Research. Terjemahan Dariyatmo, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 128 dikelola oleh Pemerintah Kota Batu atau yang dikumpulkan secara mandiri. (d) Focus Group Discussion (FGD): FGD adalah proses pengumpulan data dan informasi sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. FGD digunakan karena alasan baik filosofis, metodologis maupun praktis. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan.Pertama,tahapan reduksi data, display data dan verifikasi atau penarikan konklusi. Tahapan reduksi data adalah tahapan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terkumpul dari catatan tertulis di lapangan.Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan dimulai sebelum peneliti memutuskan kerangka konseptualwilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini. Reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian lapangan di lokasi penelitian yaitu kota Malang.Kedua, tahapan data display atau penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian yang paling sering dipakai dalam bentuk teks naratif. Awalnya informasi berwujud teks yang terpencar-pencar, seperti data hasil wawancara dengan kader atau siswa di Sekolah Perempuan Desa (SPD) serta di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu, sumber data sekunder berupa arsip yang belum tersusun dengan baik, maka peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks dalam kesatuan bentuk (gestalt) dengan konfigurasi yang mudah dipahami dalam bentuk naratif. Ketiga, tahapan verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulan yang ada diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga prinsip dari tahapan analisis data ini sifatnya sirkuler. Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga menggunakan prosedur pengujian keabsahan data yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut (1) memperpanjang masa observasi di lapangan (2) melakukan triangulasi sumber dengan mengecek antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, baik itu di Sekolah Perempuan Desa (SPD) maupun di lembaga Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu(3) mengadakan member check (4) melakukan peer debriefing, peneliti mengadakan diskusi dengan beberapa kolega peneliti. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Pendirian Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) Di tengah perubahan sosial yang kian modern, perempuan dituntut untuk mampu beradaptasi menghadapi tantangan.Predikat kaum perempuan di pedesaan sebagai “konco wingking” alias hanya bertugas mengurusi kegiatan rumah tangga, seharusnya sudah mulai ditanggalkan.Perempuan pedesaan sudah sepantasnya ambil bagian yang lebih besar dalam lingkup yang lebih luas seperti ekonomi bahkan politik.Pesan inilah yang ingin disampaikan Sekolah Perempuan Desa (SPD) yang merupakan lembaga pendidikan informal hasil gagasan aktivis perempuan dan anak—Salma Safitri Rahayyan (44 tahum, alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya-Jawa Timur) di berbagai pedesaan di Kota Batu. Ia bersama rekan-rekannya dari Suara Perempuan Desa dan Karya Bunda Community (KBC) sejak Agustus 2013 membuka sekolah informal khusus perempuan di Kota Batu. Ide SPD berangkat dari observasi yang dilakukan sepanjang tahun 2009 sampai 2012 di Kota Batu.Dalam penelitian tersebut di temukan fakta bahwa 76 persen masyarakat Kota Batu hanya mengenyam pendidikan setara SMP.Dengan latar belakang pendidikan yang rendah, pernikahan dini menjadi hal yang biasa.Akibatnya anak-anak gadis berusia 16-18 tahun sudah harus berperan sebagai istri sekaligus ibu. Melalui SPD, pendiri ingin memberikan ruang pendidikan bagi kaum perempuan. Awalnya SPD masuk ke desa-desa 129 melalui program PKK. Gayung bersambut, ternyata animo kaum ibu untuk belajar di SPD sangat tinggi. Hasil observasi yang melatarbelakangi pendirian SPD tersebut, ternyata memang sesuai dengan data bidang Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan (Dindik) kota Batu yang menunjukkan sedikitnya terdapat 1200 warga yang belum bisa membaca, tulis, dan berhitung (Calistung). Sejumlah warga buta aksara tersebut tersebar hampir merata di semua kecamatan dengan usia diatas 44 tahun dan 99 persen dari 1200 warga buta aksara dialami kaum perempuan. Penyebab buta aksara umumnya disebabkan dua faktor, yakni putus sekolah saat di bangku kelas II dan III serta tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. SPD tidak hanya berisi kegiatan arisan atau mengajarkan ketrampilan keputrian seperti perkumpulan ibu-ibu pada umumnya.Namun, SPD juga memperkaya wawasan kaum ibu lewat pengetahuan strategis dan pengetahuan praktis.Pengetahuan strategis bertujuan mengajak perempuan pedesaan berfikir lebih kritis, misalnya pendidikan mengenai Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) atau hak-hak perempuan dalam berpolitik.Sedangkan pengetahuan praktis mengajak para peserta mengenal tips-tips seputar kehidupan sehari-hari seperti kandungan gizi makanan atau sanitasi.Hingga saat ini, sekolah yang digelar sekali dalam sepekan ini diikuti oleh lebih dari 170 ibu-ibu di empat desa.Empat desa yang menjadi lokasi SPD meliputi Desa Gunungsari, Desa Giripurno, Dea Bulukerto dan Desa Sidomulyo.Sekolah Perempuan di launching pada 23 Agustus 2013, pelaksanaan program tahap pertama diselenggarakan pada Agustus – Desember 2013. pendidikan tahap kedua dilaunching pada 23 Desember 2013, proses belajar pada Januari – Juni 2014. Periode ketiga Desember 2014 – Mei 2015. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendidikan Kota Batu membekali ratusan perempuan desa melalui pendidikan non formal agar memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, pendidikan non formal merupakan sebuah pendidikan yang dikhususkan bagi para perempuan desa di Kota Batu. Pada 2015 pendidikan tersebut mewadahi sedikitnya 300 perempuan dari sepuluh dusun di sepuluh desa di Kota Batu. Tujuan Pendirian Sekolah Perempuan Sekolah Perempuan Desa (SPD) ini merupakan wadah perempuan desa dalam bertukar pengetahuan dan pengalaman(knowledge and experiences), mengenali kebutuhan dan kepentingan perempuan serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekolah Perempuan juga memiliki tujuan untuk membangun dan memperkuat kepemimpinan perempuan di pedesaan. Tujuan Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) untuk memberi pengetahuan tambahan agar perempuan desa memiliki wawasan yang luas dan memiliki keterampilan yang bisa mereka manfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan keluarga.Selain itu juga untuk membantu mewujudkan desa wisata yang memiliki ciri khas. Melalui pendidikan non formal diharapkan nantinya akan lahir generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat yang lahir dan dirawat oleh para perempuan desa yang berpendidikan dan berdaya usaha.Dengan mengikuti program pendidikan tersebut nantinya para perempuan desa mampu melihat peluang usaha di sekitarnya. Terutama usaha yang bisa mendukung sektor pariwisata seperti menciptakan produk khas desa masing-masing. Program tersebut juga akan memberi banyak manfaat bagi para perempuan desa karena ada banyak pembelajaran penting yang akan mereka terima, seperti masalah kesehatan, keagamaan, gizi anak dan lainnya. Peserta Sekolah Perempuan di SPD adalah Perempuan Usia 18 tahun keatas, perempuan dari desa atau kelurahan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.Sekolah Perempuan 130 menggunakan prinsip-prinsip feminis dan pendidikan bagi orang dewasa, menggunakan metode partisipatif, serta pengetahuan dan pengalaman perempuan menjadi sumber proses belajar. Sekolah dilakukan setiap minggu 1 kali dan dalam 1 bulan libur 1 kali. Proses pembelajaran PNFP dikelompokan dari setiap dusun dan masing-masing dusun terdiri dari 30 warga belajar dan total ada 10 dusun sehingga total ada 300 warga belajar.Kesepuluh Dusun tersebut adalah sebagai berikut: Dusun Gangsiran Tlekung, Dusun Ngukir Torongrejo, Dusun Mojorejo Mojorejo, Dusun Dressel Oro Oro Ombo, Dusun Toyomerto Pesanggrahan, Dusun Brau Gunungsari, Dusun Gandon Sumbergondo, Dusun Payan Punten, Dusun Kekep Punten, Dusun Lemah Putih Sumberbrantas.Para peserta didik setelah lulus akan mendapat bantuan alat usaha, termasuk hibah dari Dinas Pendidikan berupa 5 mesin jahit, 5 dandang (alat menanak nasi), 5 alat pembuat kue dan beberapa alat ketrampilan lainya. Sumber Dana Sumber dana Sekolah Perempuan Desa adalah dana swadaya Suara Perempuan Desa (Rural Women’s Voices) dan Karya Bunda Community (KBC) serta bekerjasama dengan individu, institusi pemerintah atau swasta, lembaga dana dari dalam negeri dan luar negeri. Pertama kali didirikan, sekolah perempuan ini belum memiliki anggaran yang resmi dan pasti, namun berbekal tekad yang kuat dan keterampilan yang dimiliki—akhirnya ada usulan pendanaan dimulai dari menjual kue dan makanan pada setiap kegiatan Sekolah perempuan.Karena, umumnya pada setiap kegiatan mendapat fasilitas makanan atau kue secara gratis, tapi berikutnya para peserta sekolah perempuan diharuskan membayar kue atau makanan yang mereka makan dengan hargaRp.2000/ kue.Dengan keuntungan sekitar Rp. 500/kue, hasilnya dikumpulkan sebagai modal beragam kegiatan bahkan saat ini di sekolah perempuan para peserta dapat meminjam uang sesuai kebutuhan. Berbeda dengan Pendidikan Non-Formal Perempuan (PNFP) semua dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan di Dinas Pendidikan. Sehingga, peserta tidak dipungut biaya apapun.Pada tahun 2015 lalu, besaran pembiayaan pendidikan non formal ini mencapai angka Rp 640 juta.Biaya ini diperuntukkan untuk transportasi pengajar, administrasi, peralatan sekolah, bahan ajar seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Para peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Pemberdayaan Perempuan di Sekolah Perempuan Desa (SPD) dan PNFP Beberapa aktivis hak asasi perempuan berbondong-bondong berjuang mendirikan komunitas.Salah satu dari kelompok itu bernama Sekolah Perempuan Desa (SPD), peserta dari sekolah ini adalah para ibu rumah tangga yang ingin mengenyam pendidikan politik secara gratis.Melalui tempat ini, benih atau embrio para politikus berpotensi muncul dari kaum perempuan desa yang awalnya sering menjadi komoditas politik sesaat.Mereka dibina, kemudian dipercaya oleh masyarakat memimpin negara atau menjalankan fungsi sebagai aparatur penyelenggara negara.Para aktivis ini menamakan dengan sebutan sekolah agar para ibu rumah tangga di desa merasakan mendapat pendidikan secara serius walaupun sebenarnya hanya berbagi ilmu melalui perkumpulan. Dengan adanya sekolah informal khusus perempuan ini, diharapkan perempuan desa tidak hanya menjadi obyek perubahan bahkan komoditas politik, tetapi menjadi (pemilih) perempuan yang kritis terutama dalam hal seperti Pilkada Kota Batu yang akan berlangsung 2017 tahun depan. Sehingga uang bukan lagi menjadi motif utama dalam berpartisipasi secara politik. Strategi orientasi kegiatan pembelajaran yang ada di Sekolah Perempuan Desa (SPD) lebih bias pada proses pendidikan politik khususnya bagi kelompok perempuan desa. Misalnya materi tentang Perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan oleh Suciwati, istri aktivis (alm) Munir yang bertempat di Omah Munir 131 (Museum HAM pertama di Indonesia).Dengan kegiatan tersebut, kelompok perempuan desa diharapkan ‘melek hukum’ dan menyadari akan pentingnya eksistensi mereka dalam mengawal tegaknya HAM di wilayah lokal. Kegiatan yang berorientasi pada pendidikan politik berikutnya adalah dengan mengadakan diskusi terbuka dengan Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 lalu. Hal tersebut penting, agar perempuan desa memahami konteks politik praktis sekaligus sebagai sarana penyampaian aspirasi, khususnya kepada para Caleg perempuan Masih dalam rangka pendidikan politik, peserta SPD juga dibekali dengan pengetahuan tentang politik anggaran, khususnya yang berkaitan dengan proses penganggaran APBD sekaligus alokasi anggaran yang ditujukan untuk kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan. Sebab, menurut hasil kajian SPD yang dilakukan secara berkala—pemerintah daerah belum menyadari pentingnya alokasi khusus bagi kelompok perempuan dan anak dalam proses pembangunan di wilayah lokal. Kegiatan pelatihan tersebut melibatkan berbagai pihak, salah satunya dengan menggandeng Malang Corruption Watch (MCW). Tidak hanya melakukan orientasi ruangan (indoor), peserta SPD juga terlibat secara langsung dalam aktivitas pendidikan politik di luar ruangan (outdoor).Misalnya dalam kegiatan aksi di gedung DPRD Kota Batu yang menolak pembangunan hotel di kawasan sumber air. Kegiatan turun lapang yang lain adalah kegiatan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2015 yang mengambil lokasi di areal alun-alun Kota Batu. Kegiatan yang dilakukan dengan aksi pembagian bunga dan orasi tersebut untuk mengingatkan kepada masyarakat akan peran dan fungsi penting tokoh perempuan dalam proses perjuangan kesetaraan di era penjajahan. Untuk mempertegas eksistensi SPD dalam memperjuangkan hak-hak kelompok perempuan khususnya di wilayah pedesaan, SPD tidak hanya melakukan kegiatan peringatan Hari Kartini, tetapi juga melakukan aksi peringatan Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret tahun 2015 dan kegiatan Peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2015. Hari Perempuan Internasional, Hari Kartini dan Hari Ibu merupakan tiga momentum paling strategis dalam rangka membangun eksistensi dan ideologi gerakan perempuan, khususnya di Sekolah Perempuan Desa. Sebab, dengan tiga peringatan tersebut diharapkan peserta, pemerintah atau bahkan masyarakat umum memahami dan menyadari arti penting sebuah perjuangan bagi kelompok perempuan dalam memperoleh hak-hak utama sebagai manusia yang berkedudukan sama dengan laki-laki. SPD menyadari bahwa latarbelakang peserta yang begitu variatif, baik dari segi pendidikan, status sosial-ekonomi dan pekerjaan tentu berkonsekuensi terhadap motivasi mereka dalam bergabung dengan Sekolah Perempuan. Pengembangan Ekonomi Lokal Selain proses internalisasi ideologi gerakan melalui kegiatan bertema pendidikan politik yang secara ekstrem berbicara tentang aksi resistensi dan oposisi terhadap kekuasaan pemerintah yang tidak berpihak kepada kelompok perempuan tetapi juga dikemas dalam kegiatan yang lebih soft, misalnya dengan kegiatan pelatihan soft skill dan hard skill bagi peserta sesuai dengan minat dan orientasi mereka. Misalnya dengan melakukan kegiatan yang lebih memahamkan peserta terhadap potensi diri dan pemahaman akan realitas lingkungan bagi kelompok perempuan. Mengingat faktor kemandirian perempuan yang tidak bisa terlepaskan dalam setiap proses perubahan yang diperjuangkan. Kemandirian akan melahirkan pribadi dan gerakan yang bebas dan merdeka tidak mudah terkooptasi dengan kekuasaan politik dan ekonomi. Perempuan bebas dan merdeka, minimal mampu memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri, tidak tergantung pada siapapun termasuk suami dalam hubungan yang sangat 132 patriarki.Salah satu dari kegiatan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan pembuatan kue dan hantaran pernikahan.Selain membekali peserta dengan ketrampilan membuat, mengemas dan memasarkan kue basah dan kue kering, dalam rangka menumbuhkan sikap kemandirian yang produktif SPD juga melakukan kegiatan pelatihan tata busana dan rias kecantikan wajah (beauty class). Program Pendidikan Non Formal Perempuan Desa (PNFP) yang telah dilaksanakan di sejumlah desa diklaim Pemerintah kota Batu berhasil membuat pendidikan perempuan di desa berkembang pesat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan kembali program tersebut tahun 2016 saat ini dengan diawali melakukan koordinasi dengan para peserta. Warga yang akan mengikuti pendidikan di tahun ini masih berasal dari dusun yang sama. Bedanya hanya pada pemberian materi.Dinas Pendidikan telah melakukan pendalaman-pendalaman materi yang diberikan.Materi pembelajaran lebih ke praktek untuk mematangkan ketrampilan yang sudah diberikan tahun 2015. Ketrampilan yang diberikan ini akan berorientasi pada potensi desa masing-masing dengan harapan akan muncul produk-produk unggulan di masingmasing dusun misalnya kegiatan membuat handycraft. Secara umum, terdapat perbedaan cukup nyata antara strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh SPD dan PNFP.Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan karena SPD merupakan lembaga swasta yang didirikan justru untuk melakukan aksi perlawanan terhadap segala bentuk penindasan terhadap kelompok perempuan.Sedangkan PNFP didirikan, dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Batu sehingga, posisi sudah jelas menjadi sub-ordinat kekuasaan pemerintah.Perbedaan latarbelakang tersebut tentu berkonsekuensi terhadap kurikulum di masing-masing lembaga.Jika SPD menyajikan kurikulum utama tentang pendidikan politik bagi peserta selain materi ketrampilan dan pengetahuan kesehatan PNFP justru banyak berorientasi pada ketrampilan kecakapan hidup (life skill) berbentuk pelatihan wirausaha (enterpreneurship) berbasis potensi wilayah. Predikat Kota Batu sebagai Kota Wisata (KWB) utama di Provinsi Jawa Timur, pemberian ketrampilan kecakapan hidup tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sektor ekonomi masyarakat agar mereka khususnya perempuan tidak hanya bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu, tentu tidak ada peluang bagi peserta PNFP untuk berada dalam posisi vis a vis dengan pemerintah kota. Padahal, dalam konteks pemberdayaan proses perubahan harus berpusat pada msayarakat dengan asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat. Proposisi di atas mengindikasikan pula bahwa inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (empowerment) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dari analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa SPD mampu memberikan pendidikan politik dengan materi yang memadai bagi perempuan desa juga beberapa pelatihan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perempuan desa demikian pula dengan PNFP. Satu hal yang berbeda dari kedua organisasi tersebut adalah kemandirian dalam pendanaan organisasi. Organisasi SPD lebih mandiri dari pada PNFP.Model rekruitmen peserta didik pada kedua organisasi ini juga sedikit berbeda demikian pula dengan model pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.Model pengelolaan organisasi yang berbeda juga membuahkan relasi yang berbeda di antara hubungan pendidik dan peserta didik. 133 5. KESIMPULAN Jika melihat konteks masalah yang dihadapi oleh kelompok perempuan khususnya di wilayah pedesaan termasuk di Kota Batu, kurikulum yang disajikan oleh Sekolah Perempaun Desa (SPD) akan jauh lebih efektif dan strategis dalam upaya memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Pendidikan NonFormal Perempuan (PNFP) yang hanya membekali peserta dengan ketrampilan kecakapan hidup (life skill) dan tentu lebih berorientasi pada keuntungan secara ekonomi (profit oriented). Atau dalam perspektif kritis, sangat rasional jika eksistensi PNFP sesungguhnya untuk melakukan upaya counter attack terhadap gerakan perlawanan dengan menentang mayoritas kebijakan kekuasaan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kelompok perempuan di Kota Batu, sebagaimana dilakukan oleh SPD melalui berbagai aksi. Artinya, PNFP hadir sebagai antitesis SPD, agar masyarakat di Kota Batu, khususnya kelompok perempuan tetap dalam posisi stagnan dan mendukung politik status quo atau tetap menjadi sub-ordinat kekuasaan pemerintah. Dengan hadirnya PNFP, kelompok perempuan di Kota Batu diharapkan mempunyai wadah alternatif bagi mereka yang tidak at home dengan doktrin resistensi atau hal-hal yang terkait dengan ideologi perlawanan kelompok sipil (civil society). Jika motif utama kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan di Kota Batu adalah ketidakberdayaan itu sendiri, maka tidak fair jika hanya menyasar sektor keberdayaan dari sisi ekonomi, karena pada hakikatnya keberdayaan manusia secara personal melintas dalam beragam dimensi seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, hukum bahkan agama dan semua itu terproses dalam sebuah sistem yang integral.Nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh SPD sudah berada dalam posisi on the track, karena perubahan yang didorong tidak hanya berorientasi pada aspek jangka pendek seperti kegiatan masak dan merias tetapi lebih pada upaya penyadaran kelompok perempuan desa akan peran dan fungsinya yang begitu penting dalam proses kehidupan. 6. DAFTAR PUSTAKA Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. 2009.Handbook of Qualitative Research.terjemahan Dariyatmo, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Harnoko, Bambang Rudi. 2012.“Pendidikan Politik Perempuan Dalam Konteks Negara Demokrasi” dalam MUWÂZÂH, Vol. 4, No. 2, Desember. Kabeer, Naila. 2001. Reflections on The Measurement of Women’s Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices. Sida Studies No3 . LSE Research Online.Swedish International Development Cooperation Agency, Stockholm, Sweden, pp. 17-57. Ketut Restini, Ni, dkk. 2014. Pendidikan Politik Berbasis Desa Adat Bagi Kaum Perempuan Di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Bulelen. ejournal.undiksha.ac.id (diakses 30 Maret 2016 ). Rai, Shirin M, Bari, Farsana. Mahtab, Nazmunessa dan Mohanty. Bidyut, 2005.“Gender Quotas and The Politics of Empowerment-A Comparative Study” dalam Woman, Quotas and Politics, edited by Drude Dahlerup. London: Routledge. Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta. 134 Salviana, Vina, dkk2004.Pengembangan Model Pendidikan Politik Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender Pada Parpol dan Ormas Organisasi Perempuan,PHB-DIKTI. 135 TRADISI PERCERAIAN: KETIDAKADILAN GENDER DAN PERLAWANAN PEREMPUAN DI SUKU SASAK LOMBOK Syafruddin Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram Email: [email protected] Abstrak Impresi awal tentang etnis Sasak yang mengesankan bagi orang luar (out group) ada pada institusi keluarga.Institusi ini kelihatannya sangat rapuh dan keretakan setiap saat menanti, seakan-akan menandai bahwa hidup berkeluarga seperti seumur jagung.Secara statistik berapa jumlah janda cerai hidup belum ada yang melakukan kalkulasi secara menyeluruh, walaupun ada itu hanya sebagian kecil saja dari mereka yang melapor bila dibandingkan dengan fakta empirik yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat (fenomena gunung es).Kesulitannya karena banyak perkawinan dan perceraian tidak diproses melalui lembaga-lembaga formal. Untuk menjawab persoalan ini, maka pertanyaan penelitian (research guestion) yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “bagaimanatradisi perceraian dan bagaimana pula perlawanan perempuan di suku Sasak Lombok”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode etnografi.Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi perceraian pada masyarakat etnis sasak dilakukan dengan pola perceraian ngerorot. Perlawanan perempuan dapat terjadi karena struktur sosial yang ada di dalam masyarakat bertindak sebagaia regulator agensi untuk melakukan regulasi terhadap tingkahlaku perempuan, sehingga martabat mereka sangat tergantung dari perijinan sosial atau a matter of social permission. Selain itu bahwa perlawan terjadi untuk mensiasati dominasi laki-laki, mereka tidak melakukan secara kelompok dan tidak pula digerakkan di dalam bingkai wadah tertentu yang dapat memberikan dan menimbulkan kesadaran pada perempuan-perempuan yang lain yang tersubordinasi. Keywords: Ketidakadilan, Tradisi Perceraian, Perlawanan perempuan 1.PENDAHULUAN Kesan tentang masyarakat Sasak bagi orang luar (out group) ada pada institusi keluarga. Institusi ini kelihatannya sangat rapuh dan keretakan setiap saat menanti, seakanakan menandai bahwa hidup berkeluarga seperti seumur jagung. Sangat berbeda dengan suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia, tidak ada tangisan anak-anak kecil yang ditinggalkan oleh ibu-bapaknya atau anak-anak yang diasuh oleh panti-panti di sudut kampung kumuh jauh dari fasilitas yang memadai karena bapak/ibunya tidak ada, kecuali beberapa kasus yang luar biasa karena ibu atau bapaknya meninggal dunia. Perceraian dalam artian normatif itu tidak boleh dilakukan karena dibenci oleh Tuhan, tapi kenyataan empirik banyak orang melakukannya. Data yang diolah dari Kantor Pengadilan Agama di kabupaten/kota di pulau Lombok dari tahun 2005 sampai tahun 2007 yaitu: Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram menunjukkan bahwa proses perceraian dalam bentuk cerai gugat (cerai atas keinginan isteri) mendapat porsi terbanyak dari semua perkara perceraian yang ada di kantor pengadilan agama di empat kabupaten/kota tersebut yaitu 88.25 % yang melakukan perceraian gugat. Sedangkan yang melakukan perceraian talak (cerai atas kemauan lakilaki) hanya 11.75% perkara perceraian dalam bentuk cerai talak. Hasil studi yang dilakukan oleh Syafruddin dkk (2009) terhadap 525 kasus perceraian, bahwa sekitar 78% perceraian dilakukan di rumah sendiri/keluarga, penghulu 136 14 %, dan hanya 2,8 % melakukan perceraian di Pengadilan agama. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian disebabkan; perselingkungkuhan 33 %, suami lari dari tanggung jawab 18 %, kekerasan dalam rumah tangga 18 %, intervesi pihak ke tiga 16,9 % dan persoalan ekonomi 13 %. Dari uraikan hasil kajian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan makalah ini adalah bagaimana pola perceraian tradisional dan bagaimana pula pola perlawanan perempuan di masyarakat suku Sasak. 2.TINJAUAN PUSTAKA 1. Perspektif Perceraian Secara etimilogis cerai dalam bahasa Inggris disebutdivorce, sering kali dipakai untuk menafsirkan kata thalaq (arab) dan sebaliknya. Terjemahan ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai salah kaprah yang menyesatkan, karena kata divorce itu asal katanya berasal dari bahasa Latin dan memberikan arti pemisahan sebuah kesatuan (unit), pemisahan fisik yang permanen dari pasangan suami-isteri, sementara itu kata thalaq dalam bahasa Arab, diambil dari kata athlaqa-ihtlaq yang bermakna melepaskan, membebaskan atau meninggalkan. Oleh karena itu thalaq dalam konteks hubungan perkawinan bermakna mengakhiri ikatan yang dibuat oleh suatu akad nikah.Sehingga kata dissolution (terputusnya) mungkin lebih tepat dipakai dari pada divorce (Jawad A, 2002,). Dalam agama tertentu yang memandang pernikahan sebagai sebuah sakramen, maka tidak dapat diputuskan, dan karenanya perceraian tidak dibenarkan. Yang menjadi masalah dalam masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai suatu kontrak dan perceraian dibenarkan, maka perceraian seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu laki-laki dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Apabila hubungan antara suami dan isteri sangat genting sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya rekonsiliasi (Ingineer, 2000). Motif dan proses perceraian di dalam masyarakat dunia sangat beragam dan kompleks. Perbedaan ini banyak dipengaruhi oleh struktur sosial, tradisi budaya dan ajaran yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Di masyarakat Indonesia berdasarkan undang-undang perkawinan tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian atau terputusnya hubungan dalam perkawinan dilakukan dengan cara; (1) cerai talak, yaitu cerai yang diikrarkan oleh suami dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggal yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk menggelar proses perceraiannya. (2) cerai gugat, yaitu cerai atas gugatan isteri, perceraian ini dilakukan oleh putusan pengadilan agama disertai alasan-alasan kenapa si isteri berkeinginan untuk menceraikan suami (Rumulyo, 1999). Perceraian dalam bentuk yang tidak formal dapat kita temukan diberbagai suku bangsa di dunia dan tindakan ini dianggap sebagai terputusnya suatu ikatan perkawinan (perceraian). Di masyarakat Zuni Meksiko, wanita setiap saat dapat menceraikan suaminya dengan cara menaruh barang-barang miliknya di luar pintu rumah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak suka lagi pada suami (Haviland, 1985). Pada masyarakat Arab suku Baduin perceraian terjadi hanya sekedar merubah arah pintu rumah dan ketika pasangan tahu tentang hal itu maka dianggap perceraian sudah terjadi (Saadawi, 2001). Goode (1991) misalnya menemukan, bahwa tingkat perceraian bisa disebabkan adanya perubahan sistem dalam keluarga, yaitu perubahan dari sistem keluarga luas menjadi sistem keluarga konjugal. Dalam keluarga konjugal ketergantungan pada kerabat yang sangat berkurang sehingga kewajiban terhadap yang tua menjadi tidak ada, akibatnya unit keluarga ini (conjugal) mudah pecah apabila terjadi konflik antara suami dan isteri 137 karena sedikitnya tekanan kerabat yang mengharuskan mereka bersatu dan mempertahankan perkawinan mereka. Dalam keluarga konjugal yang didukung oleh sistem kehidupan masyarakat yang sudah terspesialisasi kebutuhan baik suami maupun isteri di luar unit keluarga sudah banyak tersedia (seperti rumah makan, panti pijat, adanya pelayanan cuci dan jahit pakaian, diskotik, dan tempat minum dan sebagainya), memudahkan pasangan suami-isteri yang sedang mengalami konflik dan krisis perkawinan untuk bisa aktif dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa seseorang pendamping atau isteri (Karim, 1999). Tipologi yang dibuat oleh Goode tentang keluarga konjugal yang identik dengan keluarga kota di mana tingkat perceraian sangat tinggi dan keluarga luas identik dengan keluarga pedesaan sangat jauh berbeda dengan hasil penelitian Nakamura yang menemukan kecenderungan perceraian banyak terjadi di kampung yang bersifat pedesaan (rural) dibandingkan dengan kampung yang bersifat perkotaan (urban) di mana tingkat frekuensi percereian berkurang (Nakamura, 1990). Saxson (1985) juga menemukan bahwa perceraian di Amerika Serikat terindentifikasi oleh beberapa sebab seperti: latar belakang keluarga, umur pertama kawin, tingkat pendidikan, pendapatan, letak geografis, anak, dan masalah ras. 2. Perspekti Perlawanan Menurut teori androgin bahwa manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki dua unsur : andro (maskulin) dan gyne (feminim). Kedua unsur ini adalah dwi tunggal (dua dalam satu). Seorang laki-laki bisa mengekspresikan kelembutannya dan perempuan bisa mengekspresikan keberanian, bahkan agresivitas pada tingkat kelakuan tertentu, dan besar kemungkinan perempuan akan melakukan sesuatu tindakan deskruktif yang bisa membahayakan orang lain. Atau sekedar alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikenal dengan “perlawanan instrumental”25. Oleh Camara (2000) terkenal dengan teori “kekerasan memancing kekerasan”, ketidakadilan menimbulkan perlawanan dan pemberontakan oleh kaum yang tertindas dengan satu tujuan untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh kaum perempuan seperti yang di sinyalemenkan oleh Simmel bahwa tuntutan kaum perempuan sebagai suatu kelompok yang ada dalam masyarakat hanya sekedar tuntutan untuk bebas dari dominasi laki-laki, dan apa yang dilakukan oleh mereka bukan hanya bertujuan untuk menuntut kebebasan individu, tetapi juga kebebasan bagi kelompok untuk menguasai para anggotanya, dan biasanya dominasi terhadap individu oleh kelompok kecil (keluarga) dalam masyarakat jauh lebih ketat daripada dominasi oleh negara (Simmel dalam Johnson, 1998). Bagi Mernissi, hal ini terjadi karena secara ideologi keagamaan, bahwa perlawanan perempuan terhadap kaum laki-laki dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan karena implikasinya sangat besar, mereka menolak tuntutan perempuan untuk mengubah kedudukannya. Kepatuhan perempuan pada laki-laki, bukan saja hanya sarana marjinal dalam masyarakat, tetapi merupakan unsur pokok dan utama bagi kehidupan sistem tersebut (Mernissi, 1999). Untuk memahami pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah perempuan yang patuh dan tunduk, kemudian mereka menanggalkan kepatuhan, dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan laki-laki atau suami. Penelitian ini juga akan menelusurinya pemikiran Gramsci yang sangat terkenal dengan teori hegemoni dan kontra hegemoni. Teori ini akan dipergunakan bukan dalam artian untuk menguji teori, akan tetapi 25 Semacam perlawanan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan/diperlukan tanpa melakukan tindakan destruktif. Erich Fromm. “Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia”(terj). Yogyakarta, Pustaka Pelajat, 2000, hal, 292 138 lebih dipandang sebagai suatu perspektif atau kacamata untuk melihat, mengkaji dan menelaah peristiwa perceraian sebagai suatu simbol penolakan dan perlawanan perempuan sebagai isteri terhadap kekuasaan laki-laki. Gramsci (dalam Budiman,1982) membagi dua jenis kekuasaan: (1) kekuasaan hegemoni atau kekuasaan yang diperoleh dengan persertujuan dari orang-orang yang dikuasai; (2) kekuasaan yang diperoleh melalui pemakaian kekuatan fisik. Kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan kekuasaan hegemoni dalam pengertian Gramsci, karena perempuan sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai suatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa wanita tunduk kepada mereka. Hegemoni selamanya bisa saja dominan akan tetapi tidak akan pernah total, karena selalu mendapatkan tantangan. Oleh karena itu, jika konsep patriarki dianggap sudah menghegemoni dalam masyarakat, maka hal ini tetap saja akan mendapat tantangan dan tidak akan pernah dianggap sebagai suatu sistem yang tetap, dan baku (Sushartami, 2002). Selanjutnya sangat perlu untuk menjajaki lebih lanjut tentang adanya sebuah hegemoni alternatif- hegemoni tandingan (counter-hegemony) yang muncul dari kelompok atau kelas yang dikuasai, yang merupakan kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (tereksploitasi dan tersubordinat) yang dapat melakukan penyusunan dan perlawanan. Kelompok atau kelas yang dikuasai ternyata mampu menciptakan struktur-strukturnya sendiri serta menafsirkan realitas sosial menurut pengalamannya, sesuatu yang cenderung diabaikan. Selanjutnya perlu dipertimbangkan kembali konsep kekuasaan yang oleh kebanyakan orang dipahami dalam pengertian negatif. Kekuasaan juga bisa dikaji dalam kemampuan-kemampuan yang positif dan produktif. Hal ini akan memungkinkan memperluas pemahaman mengenai hegemoni dan kontra-hegemoni. Kontra-hegemoni dari kelas yang dikuasai juga bisa dipahami sebagai pernyataan atau dikursus perlawanan (counter-discourse), di mana perjuangan melawan praktek-praktek diskursif dan kekuatan pendisiplinan terjadi baik dalam produksi simbolis maupun dalam hubungan sosial (Simon, 2000, Hikam,1990, Budiman, 1982). Pertanyaan yang akan muncul dan menggugah pemikiran penulis dalam kajian tentang perlawanan perempuan terhadap struktur sosial patriarki, mengapa perempuan membangkang pada kekuasaan laki-laki sebagai suami, dan mengapa pula mereka menanggalkan kepatuhan atau mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan ini sekurang-kurangnya ada dua konsep teoritis yang berusaha menjelaskannya. Pertama, berusaha menjelaskan fenomena perlawanan dari pandangan mengenai otoritas moral sebagai basis dari hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial.Kedua, mendasarkan penjelasannya pada adanya keharusan struktural sosial budaya yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku individu, termasuk perlawanan terhadap kekuasaan laki-laki. Pada perspektif otoritas moral bahwa perlawanan dan pemberontakan dapat terjadi karena adanya kebiadaban moral dalam masyarakat. Sebaliknya, pada pendekatan kedua bahwa perlawanan dan pemberontakan terjadi karena didasarkan pada adanya rangsangan eksternal sebagai faktor utamanya (Hikam, 1990). Selain dari kedua faktor di atas, untuk menjelaskan fenomena perlawanan, menurut Moore (Hikam, 1990) bahwa setiap masyarakat mempunyai suatu “moralitas alamiah“ yang sudah ada jauh sebelum adanya pengaruh sosial tetapi belum tentu mempunyai keunggulan untuk memecahkan masalah tersebut, moralitas alamiah ini tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebiasaan dan kondisi sosial. Melalui moral semacam ini sebaliknya memberikan dorongan bagi terjadinya perkembangan aturan-aturan moral, kemarahan moral, dan persepsi-persepsi mengenai ketidakadilan di dalam setiap masyarakat. 139 Studi yang dilakukan oleh Uma Chakravarti pada masyarakat kasta India, seperti yang dikutip oleh Kamla Bhasin dalam bukunya “menggugat patriarki” (1996), menemukan bahwa dalam masyarakat kasta India kontrol terhadap perempuan dilakukan melalui tiga sarana yang berbeda dan berlangsung pada tingkatan yang berlainan. Pertama adalah ideologi, di mana ditanamkan ke dalam kepribadian perempuan sebagai pativrata (kesetiaan ibu), dengan ideologi ini perempuan menerima dan menginginkan kesetian ibu sebagai ekspresi tertinggi dari kepribadian mereka, melalui mekanisme ini pula status rendah mereka dibuat tak terlihat dan sistem patriarki dengan kuat ditegakkan sebagai ideologi yang kelihatannya alamiah. Sarana kedua ialah hukum dan adat kebiasaan, hal ini sangat ditentukan oleh tata sosial Brahmanis untuk membuat perempuan yang menyimpang tetap berada di dalam kontrol patriarki. Sarana ketiga ialah negara, jika laki-laki yang diberikan hak untuk menggunakan kekuatan tidak berhasil mengendalikan seorang perempuan, maka negara kuno menegakkan berlakunya norma-norma patriarkal dengan menghukum perempuan karena melakukan pelanggaran batas-batas sebagaimana yang didefinisikan oleh kaum laki-laki. Moore seperti yang dikutip oleh Hikam (1990), misalnya melihat bahwa perlawanan terjadi di dalam suatu masyarakat karena adanya suatu kebiadaban moral. Kebiadaban moral terjadi diakibatkan adanya problem ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan sosial merupakan suatu penyimpangan (derivasi), pengertian dari keberangan moral yang dipengaruhi oleh tiga elemen dalam suatu sistem sosial: 1) Koordinasi sosial atau kekuasaan. Pada dimensi ini perlawanan dan pemberontakan terjadi jika seseorang atau perempuan (isteri) merasa bahwa kekuasaan laki-laki sebagai suami misalnya tidak lagi memenuhi kewajiban moral yang mendasar. 2) Kegagalan untuk menangani kesenjangan sosial yang mengakibatkan keberangan moral, dengan mengambil bentuk pengutukan atau protes secara terang-terangan maupun tersembunyi. Misalnya lakilaki (suami) gagal memenuhi kebutuhan akan penghargaan, tidak diperhatikan dan tidakadanya kasih sayang. 3) Distribusi sumber daya yang tidak adil,di sini bahwa persamaan memainkan peranan sebagai suatu bentuk jaminan sosial, karena setiap manusia selalu dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas. Suami tidak bisa secara tepat mengalokasikan sumber daya yang ada antara keluarga (orang tua, ingat dalam keluarga luas) dengan perempuan sebagai isteri. Kegagalan suami untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan kekecewaan dan keberangan moral perempuan. Berbeda dengan Milgram (dalam Hikam, 1990) mengatakan bahwa perlawanan dan pemberontakan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu keharusan struktural yang akan menentukan tindakan-tindakan dan perilaku individu-individu. Termasuk perlawanan terhadap kekuasaan (dianut oleh kaum strukturalisme baik mazhab Marxis maupun yang non-Marxis), penolakan dan perlawanan terjadi didasarkan pada adanya rangsangan luar sebagai faktor utama yaitu perangkat hukum dan paksaan dari luar. Untuk melaksanakan tindakan penolakan dan perlawanan oleh para kelompok perempuan yang termarginalisasi, tereksploitasi dan tersubordinasi. Mereka biasanya akan menggunakan dan memanfaatkan norma-norma dan sistem-sistem nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat untuk melawan dominasi kelompok laki-laki, hal itu dilakukan karena pada diri mereka memiliki penafsiran-penafsiran tersendiri mengenai kewajibankewajiban moral yang berakar pada tradisi budaya yang meraka alami atau lihat di dalam masyarakat. Kemungkinan hal ini akan menjadi senjata bagi kaum perempuan untuk melakukan penolakkan atau ketidaksetujuannya terhadap perilaku laki-laki sebagai suami. Peristiwa ini oleh Henrieatta L. Moore (1998), seperti yang ditulis dalam bukunya “ Feminisme and Antropology” (terj), ia menyebutnya sebagai “ bentuk hari-hari perlawanan wanita”. Menurutnya bahwa penolakan atau perlawanan perempuan (isteri) terhadap suami dapat dilakukan mulai dari penolakkan untuk memasak, penolakkan untuk 140 berhubungan seksual, meninggalkan pekerjaan rumah tangga, dan pertanian, serta menyebarkan gosip-gosip tentang pasangan-pasangan mereka. Demikian pula studi yang cukup menarik dilakukan oleh Loan Lewis pada masyarakat muslim Somali di Timur laut Afrika yang besistem kekerabatan patrilineal. Seperti yang dikutip oleh Moore (1998), yaitu apa yang mereka disebutkan “kerasukan roh”, yaitu suatu kajian tentang bagaimana keterlibatan perempuan-perempuan yang sudah bersuami tentang “kerasukan roh”. Perlawanan perempuan dengan menggunakan kerasukan roh sebagai instrumen perjuangan mereka untuk mempertahankan hidup dan memberi makan anak-anak dalam lingkungan yang keras karena diabaikan oleh suami yang sering tidak ada dan di mana mereka dirusak oleh ketegangan-ketegangan perkawinan poligini yang dilakuan oleh para suami, dan kerentanan akses kaum perempuan pada sumber daya di luar perkawinan. Menurut Lewis kerasukan roh dapat dikatakan sebagai suatu penghindaran yang terbatas untuk menentang penyiksaan dari adanya pengabaian dan penderitaan dalam hubungan konjugal yang sangat bias laki-laki. Perempuan terpaksa menggunakan kerasukan roh sebagai cara yang tidak langsung untuk mengutarakan keluhan-keluhan mereka kepada suami dan cara untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, hadiah dan sebagainya.Oleh Simone De Beauvoir (1999) hal ini dilakukan oleh kaum perempuan dalam bentuk agitasi simbolis, karena kaum perempuan dalam melakukan protes dan penolakan terhadap kaum laki-laki kurang memiliki tujuan yang konkrit untuk mengorganisir diri menjadi sebuah unit yang dapat berhadap-hadapan dengan unit kolektifitas. 3.METODE PENELITIAN Penelitianini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan pendekatan ini dapat menunjukkan tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, pergerakanpergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Oleh Strauss dan Corbin (1997) digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena atau gejala yang ada. Untuk mempelajari secara mendalam peristiwa sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat suku Sasak, yaitu perceraian penulis menggunakan metode penelitian etnografi (Spradley,1997).Dengan demikian etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan, dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Agar peneliti terhindar dari bias subyektif dalam melukiskan suatu peristiwa sosial budaya, maka peneliti menggunakan perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif emik peneliti mendeskripsikan peristiwa sosial budaya dari sudut pandang orang “mata kepala” warga masyarakat setempat yang diteliti, sedangkan perspektif etik peneliti mendeskripsikan berdasarkan konsep dan pandangan orang luar (kacamata orang lain). Dalam penelitian ini informan dan subyek26penelitian bersifat pilihan atau criterium based selection. Informan dan subyek penelitian tidak untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Dalam hal ini peneliti memilih informan penelitian yang dipandang paling mengetahui dan memahami masalah yang dikaji, informasi yang diperoleh dari mereka (informan) sebagai salah satu sumber untuk mencari untuk keabsahan data melalui proses triangulasi yang tidak hanya mengandalkan informasi 26 Pada penelitian ini tidak menggunakan konsep responden, karena tidak menguji hipotesis dan tidak membatalkan suatu hipotesis tertentu, dan juga tidak menggunakan konsep pelaku karena seorang pelaku adalah seseorang yang menjadi obyek pengamatan dalam suatu setting alam. Bekerja dengan Subyek dimulai dengan ide-ide yang ditetapkan sebelumnya; bekerja dengan informan dimulai dari ketidaktahuan. Subyek tidak mendefinikan hal-hal penting yang harus ditemukan oleh peneliti; informan mendefinikannya. Hal ini dapat dibaca dalam bukunya Spradley “Metode Etnografi” (terj), hal, 38-29, 1997. 141 tunggal dari subyek penelitian, tetapi perlu informasi yang jamak dari banyak sumber data, dan didayagunakan untuk melengkapi, cross-check dan memahami peristiwa perceraian dalam komunitas masyarakat sasak secara umum. Subyek penelitian adalah merekamereka yang mengalami secara langsung peristiwa Perseraian.Informan dan subyek penelitian, dipilih melalui dua tahap. Pertama, akan dicari informan “typical group” yang dianggap mengetahui dan memahami tentang peristiwa perceraian. Kelompok seperti ini adalah tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan pada tahap ini dilakukan secara purposif sampling maupun snow ball. Pengumpulan data yang paling utama dipergunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi yang telah digunakan bersifat partisipasi moderat, dilakukan secara fleksibel, sesekali berpartisipasi secara tengahan dan waktu lain secara pasif. Wawancara dapat memungkinkan peneliti untuk dapat menggali apa-apa yang diketahui maupun yang dialami oleh seseorang subyek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri mereka (explicit knowledge maupun tacit knowledge). Kedua. dengan wawancara peneliti dapat menanyakan kepada subyek dan informan hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang. Ketika wawancara berlangsung, peneliti berusaha untuk memahami local knowledge, menggunakan sebanyak mungkin empathy, dan memahami sesuatu dengan cara pemahaman setempat. Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya ialah pengolahan data sehingga dapat dilakukan analisis. Pengolahan data dimulai dengan melakukan klasifikasi data, dan merumuskan kategori-kategori (kelas-kelas) yang terdiri dari gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam suatu klasifikasi peneliti membedakan antara masing-masingmasing kategori dan sub-kategori (Vredenbregt,1981). Atau oleh Muhadjir (1989) yaitu dimulai dengan melakukan penyatuan dalam unit-unit, dengan berpegang pada dua prinsip yaitu; heuristik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Unit-unit terhimpun liwat catatan hasil (observasi, wawancara, dokumen, rekaman, komentar peneliti dan lainnya), dan kemudian kategorisasikan. 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1. Tradisi Perceraian Faktor sosial budaya dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku suatu masyarakat, betapa tidak karena secara sosial bahwa habitus yang dipelajari secara turun-temurun dan disosialisasikan (dipelajari). Demikian juga dengan perceraiansebagai impak dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat yang mendahului aktor (manusia) dapat memberikan drive pada munculnya perilaku yang lain.Pada suku Sasak, ketika seorang seorang perempuan ingin bercerai dengan suami maka di dalam masyarakat terdapat pranata tradisional yaitu ngerorot27. Hasil penelitian menemukan bahwa ngerorot yang dilakukan oleh isteri membentuk dua pola yang berbeda-beda. (1)ngerorot nenangin diriq, si isteri hanya sekedar untuk mengingatkan suami agar mengadari kekeliruan dan sebagai sarana 27 Ngerorot secara umum dipahami isteri pergi meninggalkan rumah tampa pamit pada suami dan anggota keluarga lain, hal ini dilakukan oleh isteri karena keberatan atau tidak senang terhadap kelakuan suami. Ngerorot juga dapat dikatakan sebagai proses awal dari terjadinya perceraian karena dengan melakukan ngerorot dapat dipandang sebagai usaha penghindaran diri dari hubungan dengan suami (avoidensi relationship) dan mempermudah terjadinya perceraian. Ngerorot identik dengan cerai lari yang merupakan lawan dari konsep merariq ye memaling (kawin lari) yang merupakan perilaku yang umum dilakukan oleh masyarakat Sasak apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan. 142 untuk menenangkan diri agar masing-masing pihak yang bertikai tidak terlibat pada pertentangan yang membahayakan hubungan. (2)ngerorot yang dilakukan oleh isteri sebagai isyarat bahwa isteri menginginkan perceraian (sasak. ngerorot kemeleq seang) dari suaminya. 1) Ngerorot Nenangin Diri (ngerorot menenangkan diri) Pola ini masih bersifat temporer, seorang isteri yang melakukan ngerorot masih dihadapkan pada ambivalensi pilihan, yang dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang sama yang sulit dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam perspektif teori konflik Simmel hal ini terjadi karena masih adanya rasa cinta (loving) dan bercampur dengan perasaan benci (hating) isteri terhadap suami. Ngerorot ini seorang isteri tidak atau belum sampai memiliki niat untuk mengakhiri hubungan dengan suaminya (cerai), dan kemungkinan untuk terjadinya harmonious relationship (kerukunan) masih terbuka luas bagi kedua belah pihak.Pada pola ini (ngeorot nenengin diriq), pertentangan di antara suami dan isteri belum mengarah pada terjadinya pembubaran atau perpisahan perkawinan (perceraian), karena di antara mereka masih bisa ditemukan celah kompromi yang dapat mempersatukan mereka kembali sebagai suami isteri. Ngerorotnenangin diriq dilakukan sebagai usaha dari seorang isteri untuk meredakan ketegangan dan pertentangan yang terjadi antara suami dan isteri atau bisa juga antara isteri dengan keluarga dari pihak suami. Pola ngerorot ini dapat disebut sebagai suatu circumvention (perilaku menghindari suatu keadaan dengan maksud mencapai tujuan lain yang mungkin bertentangan).Pada momen ini biasanya seorang isteri akan pergi meninggalkan rumah tanpa ada suatu restu dan izin dari suami dengan tujuan ingin menyelamatkan rumah tangganya karena seorang isteri masih mencintai suami dan keluarganya. 2) Ngerorot Kemeleq Seang(Ngerorot ingin bercerai) Pola ngerorotkemeleq seangbersifat permanen.Hubungan duan (dyad) pada tingkat mikro suami-isteri engalami krisi yang luar biasa yang ditandai oleh terjadinya pertentangan atau konflik di antara suami dengan isteri. Apa yang dilakukan oleh perempuan (isteri-isteri) memberikan indikasi bahwa seorang isteri melakukan penghindaran diri pulang ke rumah orang tua secara sembunyi-sembunyi menggunakan kendaraan pranata ngerorot misalnya, dapat merupakan instrumen atau alat guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, walaupun oleh si isteri belum atau tidak dinyatakan secara nyata dan terusterang dihadapan orang lain (suami atau keluarga). Artinya ngerorot yang dilakukan oleh seorang isteri di mana ngerorotnya sendiri bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai batu loncatan untuk meraih tujuan yang lebih fungsional yang merupakan dambaan dari subyek penelitian itu sendiri, misalnya si isteri tidak tahan lagi dengan perlakuan suami, ingin bebas, ingin bercerai, atau bisa jadi dia ingin kawin lagi dengan laki-laki lain yang lebih baik dan bertanggungjawab. Pada pola ini isteri melakukan ngerorot dapat dianggap sebagai tindakan simbolis bahwa seorang isteri tidak bisa lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dan secara tidak langsung ia menginginkan perceraian dari suaminya. Ngerorot ini dilakukan karena secara emosional seorang isteri tidak tahan lagi dengan tindakan dan situasi lingkungan suami. Cara ini dilakukan karena dengan meninggalkan suami dan pulang ke rumah orang tua, si suami dengan sesegera mungkin dapat menceraikannya. Artinya pertentangan yang terjadi sudah akan mengarah pada terjadinya pembubaran perkawinan sebagai sebuah institusi keluarga. Pola ngerorot yang kedua ini biasanya si isteri tidak mau kembali lagi pulang ke rumah suami, walaupun pada akhirnya nanti si isteri menerima resiko yang akan 143 mengakibatkan pada terajadinya family disorganization, yaitu suami akan menceraikan (talak) isterinya. Pertentangan dan terjadinya ngerorot pada pola ini (ngerorot kemeleq seang), di mana pihak-pihak (suami-isteri) kelihatannya tidak ada lagi kesamaan yang dapat dipertemukan sehingga sebuah kompromi tidak dapat dicapai, dan masing-masing dari mereka ( suami isteri) akan mencari jalan sendiri-sendiri sehingga perpisahan dan pembubaran perkawinan tidak dapat terelakkan lagi (cerai). Ngerorot kemeleq seang (ngerorot ingin bercerai) dipahami sebagai suatu tindakan simbolik dari seorang isteri yaitu meninggalkan arena konflik (rumah suami) ke rumah orang tuanya, baik secara fisik maupun psikogis untuk selama-lamanya (permanently). Tindakan ini berfungsi untuk meminta cerai kepada suaminya karena dengan meninggalkan arena konflik si suami dengan cepat dan mudah mengeluarkan kata-kata cerai yang sudah lama diharapkan oleh seorang isteri. Tradisi perceraian dalam konteks sosial budaya masyarakat suku Sasak, bahwa suatu perceraian baru bisa terjadi kalau si suami sudah mengatakan kata-kata cerai (Sasak. Seang), karena menurut pemahaman masyarakat sahnya suatu perceraian kalau si suami sebagai laki-laki sudah mengikrarkan dengan lafal kata-kata cerai (sasak.seang). Kondisi sosial masyarakat yang demikian menandai bahwa suatu perceraian berada di tangan lakilaki sebagai suami. Pemahaman ini muncul dari adanya penafsiran tekstual yang biasa terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (patriarki).Mereka mengatakan kalau si suami belum mau melaflkan kata-kata cerai, sementara ngerorot si isteri sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka perceraian atau talak tidak bisa dilakukan dan belum dianggap sah oleh masyarakat. Pada tataran ini, dan akibat kesalahan di dalam menafsirkan ajaran-ajaran yang dianut, maka ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama pada kaum perempuan. Padahal secara konseptual dan implementatif diakui oleh para intelektual muslim, bahwa terputusnya tali ikatan perkawinan tidak semata-mata hak laki-laki (suami), tetapi juga menjadi hak perempuan (isteri), baik dalam bentuk thalak al-tafwid, khulu’, dan fashak (Jawad, 2002, Engineer, 2000).Dua pola perceraian tradisional suku sasak (ngerorot nenangin diriq dan ngerorot kemeleq seang), terlihat suatu keberanian moral dari seorang isteri untuk melakukan perlawanant. Hal ini dapat memberikan isyarat kepada kita bahwa konflik atau pertentangan yang terjadi dalam hubungan intim di antara suami dengan isteri telah memasuki nilai-nilai inti dari tujuan perkawinan itu sendiri. Meminjam istilah Coser, hal ini dapat disebut dengan konflik fungsional negatif, yaitu suatu konflik yang sudah memasuki wilayah atau ruang dan menyerang nilai-nilai dasar dari hubungan. Perkawinan dengan tingkat keakraban dan keintiman dari mereka telah dirusak oleh adanya pengingkaran dari nilai-nilai inti perkawinan seperti; suami berani pacaran dengan perempuan lain, suami ingin kawin lagi, suami telah melakukan kekerasan terhadap isteri. Problem ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap komitmen perkawinan sebagai institusi sosial di mana satu sama lain untuk dapat berbagi suka dan duka. Pada pemahaman ini melahirkan proposisi “bahwa pertikaian yang ditimbulkan oleh adanya pengingkaran nilai-nilai inti kesepakatan bersama dari hubungan perkawinan, maka pertikaian itu akan menjadi keras sulit untuk terjadinya akomodasi” 2. Perlawanan Perempuan Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya perlawanan perempuandimasyarakat suku sasak disebabkan oleh faktor: (a) adanya biadaban moral atau otoritas moral, (b) adanya keharusan struktural atau Otoritas Struktural. a) Otoritas Moral Perlawanan 144 Sebuah keluarga didirikan untuk menjadi alat manusia mencapai kesejahteraan, kecintaan dan keadilan antara peran laki-laki (suami) dan apa yang diperankan oleh perempuan (isteri). Namun pada kenyataannya justru berlawanan dengan keadaan sebenarnya yang diinginkan oleh manusia. Keluarga sebagai institusi sosial menjadi sebuah kekuatan yang besar dan kejam yang menindas hak-hak warganya, membelenggu kemerdekaan dan merampas rasa keadilan. Bila demikian yang terjadi, yang perlu dipertanyakan masih adakah kesetiaan dan kepatuhan pada lembaga ini (keluarga) yang bisa dipertahankan. Kesetiaan yang diberikan oleh perempuan (isteri) kepada keluarga terutama laki-laki (suami) dalam kondisi yang demikian, yang pada ujung-ujungnya akan memupuk rasa kekecewaan dan putus asa, dan kemungkinan yang tersisa dalam jiwa perempuan hanyalah sebuah hasrat untuk melawan dan melakukan pemberontokan, walaupun hal itu masih terbungkus rapi dalam kesetiaan yang semu, pada akhirnya mereka bisa melakukan perlawanan terbuka. Fenomena ngerorot padaperceraian tradisional yang dilakukan perempuan Sasak yang menggunakan institusi tradisional adalah lubang kecil yang paling bisa dipahami (understandable), yaitu cara di mana perempuan (isteri) dapat mengurangi tekanan dari institusi keluarga dibawa cengkeraman laki-laki (suami). Pada konteks ini terjadi kolonisasi yang telah melakukan rasionalisasi dunia kehidupan dengan melakukan pencerahan moral di bawah payung ijtihat legitimasi religius yang missogenis (membenci perempuan) dan androsentris (memihak laki-laki), sehingga seakan-akan terjadi pemaksaan sosial (social consraint) yang mendepersonalisasi manusia lain yaitu kaum perempuan (Casado da Rocha A.L, 2002, Ritzer G dan Douglas J. G, 2004, Jawad A, 2002). Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan di dalam keluarga yang semuanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, hukum dan politik,disamping oleh kekuatan-kekuatan psikologi dan biologis yang mendorong terbentuknya keluarga, kaum perempuan secara rutin merupakan bawahan dalam institusi keluarga dan kemudian merupakan bawahan dalam dunia publik. Sekalipun kaum perempuan tidak dapat mematuhi keinginan dari laki-laki (suami) tanpak pasif, sungkan, dan diam, mereka dapat saja menolak kondisi yang mereka tidak sukai, melalui cara penghindaran diri (evoidensi relationship), atau tidak mengindahkan segala apa yang disuruh oleh suami-suami mereka. Bentuk penolakan dan ketidakpatuhan secara diam atau terselubung dari eksploitasi kaum laki-laki (suami) adalah lebih umum dilakukan dari pada secara terang-terangan. Walaupun kadang-kadang para perempuan akan bersedia menanggung resiko dengan mengadakan konfrontasi langsung bila mereka menganggap ketidakadilan tidak dapat lagi memenuhi aspek psikologis, kultural, dan moral. Apa yang dilakukan oleh perempuan Sasak dengan ngerorotdan perlawanan dapat dikatakan sebagai suatu penemuan sosial yang harus diakui dan dihargai karena dengan melakukan perceraian dianggap sebagai bentuk pengamanan bagi ketegangan dan konflik yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri dan juga menjadi simbol budaya penolakan perempuan terhadap dominasi idiologi yang bias, yang hanya menampilkanperempuan sebagai isteri, ibu rumah tangga yang patuh dan penurut serta menerima apa adanya dari suami, yang di masyarakat kita fenomena ini cukup dikenal dengan konsep ibuisme atau hausewifizatio28. Dalam studi ini ditemukan beberapa indikator otoritas moral perlawanan perempuan (isteri) yang mendorong terjadinya perceraiandengan mengambil ruang 28 Konsep ini telah digunakan oleh negara pada jaman orde baru dibawah payung program pemerintah seperti PKK, Darma wanita dan Isteri sebagai pendamping suami, wanita sebagai tiang negara, sehngga seakan-akan melokalisasi peran dan status perempuan di seputur kegiatan-kegiatan domestik sehingga membatasi peren dan status perempuan pada sektor lain. 145 konfrontasi yang terbuka, hal ini dilakukan karena: (1) hilangnya kewibawa kepala keluarga (suami), suami tidak lagi memenuhi dan melakukan kewajiban-kewajiban moral yang mendasar terhadap keluarga, seperti suami lari dari tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan material dan isteri dibiarkan untuk menanggung bebannya sendiri tanpa ada sokongan dari suami. (2) Isteri tidak lagi memperoleh atau gagal memenuhi kebutuhan akan penghargaan dari suami, seperti tidak diperhatikan dan tidakadanya kasih sayang. (3) tidakadanya distribusi sumber daya yang adil, sehingga isteri gagal memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan, karena suami tidak bisa menempatkan secara proporsional antara keluarga (orang tua dan lain-lain) sebagai suatu relasi yang agak terpisah dengan kehidupan isteri sebagai teman, kolega, dan tempat saling tukar menukar pengalaman suka dan duka di dalam mengarungi bahtera kehidupan. b) Otoritas Struktural Perlawanan Otoritas struktural memandang bahwa ketidakpatuhan dalam masyarakat karena adanya keharusan struktural yang akan menentukan semua tindakan, dan perilaku individu. Dalam pengertian yang luas bahwa ada faktor ekternal yang dapar menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan seperti institusi-institusi sosial dan perangkat hukum yang ada di dalam masyarakat. Oleh Smith bahwa apa yang terjadi pada berbagai jenis kehidupan sehari-hari manusia dibentuk oleh struktur makro dan struktur makro ini dibentuk oleh sejarah, kebutuhan ekomoni dan kebudayaan ( Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2003). Pada tataran empirik struktur sosial biasanya selalu memainkan perannya sebagai a regulatory agency, semacam badan yang mengatur perilaku manusia dengan menyiapkan prosedur yang memberi pola bagi perilaku manusia, dipaksakan untuk berjalan di dalam alur- alur yang dianggap patut oleh masyarakat ( Berger, 1990). Maka tidak mengherankan di dalam struktus sosial yang patriarkhi, bahwa terjadinya ketidakadilan gender yang ditandai adanya relasi kuasa laki-laki yang dominan terhadap perempuan, hubungan laki-laki dengan perempuan di dalam masyarakat adalah hubungan politik, yaitu suatu hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat dimana satu kelompok manusia dikendalikan kelompok manusia lain dan lembaga yang utama dari sistem patriarki adalah keluarga. Dalam keluarga seorang laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga, di dalam keluarga juga ia mengontrol seksualitas, kerja atau produksi, reproduksi dan gerak perempuan. Terdapat hirarkhi lakilaki lebih tinggi dan berkuasa, perempuan lebih rendah dan dikuasai. Maka dengan demikian akan memunculkan hirarki, subordinasi, dan diskriminasi. Walaupun para perempuan melakukan usaha pengakuan tandingan (counterrecognition) tetapi karena struktur sosial sudah menjadi baku dan terinternalisasi atau tertanam begitu lama, dan kuat, maka martabat manusia seperti kaum perempuan sangat tergantung dari adanya suatu perijinan sosial dalam struktur makro yaitu masyarakat atau oleh Berger (1994) disebut sebagai a matter of social permission. Sehingga pandangan tentang dunia mereka sangat ditentukan secara sosial (word taken for granted ) bukan oleh kehendak individu atau pribadi . Pada studi ini bahwa hegemoni laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) pada masyarakat Sasak Lombok banyak menggunakan legitimasi religious29 dan adat untuk melakukan pembenaran terhadap perbuatan mereka. Di dalam masyarakat misalnya berkembang pemahaman yang diperoleh dari para tokoh agama, bahwa isteri maupun suami tidak boleh mengatakan “seang” (cerai) pada pasangannya karena pada saat itu pula 29 Istilah legitmasi adalah semacam pengetahuan yang diobyektivasi secara sosial yang bertindak untuk menjelaskan dan membenarkan tatanan sosial. Walaupun dalam pelegetimasian ini terjadi krisis toelogi, sehingga terjadi paradok keterasingan religius yang seakan-akan justru terjadi proses dehumansisasi dan depersonafikasi dunia sosiokultural. Dapat diperdalam dalam bukunya Berger “Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial, hal, 34 dan 121, tahun, 1991. 146 talak sudah dijatuhkan. Kata ”seang” (cerai) seakan-akan memiliki nilai sakral dan tabu, artinya kata ini tidak boleh diucapkan pada sebarang tempat, situasi dan kondisi, baik serius maupun hanya sekedar main-main yang mengarah pada isteri-suami karena Tuhan akan marah. Dan akan menjadi tabu karena kalau diucapkan akan berakibat dari terjadinya perceraian. Demikian juga halnya, di dalam masyarakat banyak yang menganggap bahwa urusan keluarga adalah urusan suami yang walaupun dipukul tidak perlu dilaporkan pada orang lain, karena suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah hak milik suami, sementara di dalam ajaran-ajaran agama kalau si isteri melakukan nusyud (tidak patuh dan membangkang) dibenarkan seorang suami untuk memberikan peringatan walaupun dengan cara memukul. Perempuan (isteri) tidak berhak untuk menolak terhadap kata-kata cerai dari suami, karena menurut mereka perceraian adalah hak suami dan perceraian bisa terjadi kalau suami sudah menjatuhkan kata-kata cerai dan Tuhan akan meridoiNya. Banyak dari mereka yang melakukan perkawinan dan perceraian syah hanya menurut agama walaupun tidak dicatat secara formal dalam agenda negara. Pada tataran ini di dalam masyarakat terjadi semacam mysthical norm, yaitu dengan memistifikasi norma-norma dan mengaburkan apa yang sesungguhnya terjadi (Berger, 1985b). Dengan suatu harapan agar terjadinya culture expectation, yaitu harapan budaya agar suatu kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dimana kepada seluruh anggota komunitas untuk bertingkah laku sesuai adat istiadat yang berlaku. Menguaknya fenomena ngerorot pada institusi perkawinan di masyarakat Sasak Lombok dapat dikatakan sebagai bentuk protes terbuka yang merupakan jawaban dari tejadinya kebiadaban moral, problem ini muncul karena adanya ketidakadilan dan penyimpangan dari komitmen kehidupan perkawinan. Institusi perkawinan tidak bisa lagi menopang kewajiban-kewajiban moral, seperti suami berani pacaran (sasak. Midang), dan melakukan perkawinan lagi. Struktu sosial yang tidak memberikan kebebasan perempuan (isteri) untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak, dan tidak memihak kepada perempuan, kuatnya kungkungan adat, tradisi serta tidak adanya proteksi sosial yang dapat menjamin keberlangsungan hidup keluarga. Kegagalan pada dua dimensi ini (otoritas moral dan otoritas struktural) akan dapat menimbulkan kekecewaan-kekecewaan dan terjadinya keberangan moral (tidakpatuh dan protes terbuka) dengan mengambil ruang “avoidensi relationship (penghindaran diri), atau melakukan ngerorot/seang. Walaupun pada posisi ini perempuan akan mendapatkan konsekuensi yaitu terjadinya divorce (perceraian) dari suami-suami mereka. Untuk sementara posisi ini kemungkinan dapat memberikan keuntungkan perempuan (istri) dari subyek pelaku (rejim moral), karena mereka dapat keluar dari lilitan perkawinan yang penuh dengan kebohongan dan kecurangan. Dan ketika mereka keluar dan berhadapan dengan institusi masyarakat, di sana mereka telah ditunggu oleh status dan stigma sosial yang hanya memandang mereka secara one side issue (satu sisi) entitas atau keberadaan mereka. Status janda dengan bebagai anekdot dan pelabelan di dalam masyarakat yang lebih banyak memposisikan mereka secara negatif dan terpinggirkan (marginalisasi) seperti; janda Malaysia (jamal), dan janda Arab (jarab), janda lokal (jalok), bahkan ada yang mengatakan sebagai penggoda suami-suami orang30. 30 Istilah yang diberi singkatan Jamal ( janda Malaysia) atau Jarab ( janda Arab) merupakan istilah yang sering kali menjadi bahan tertawaan bagi kebayakan laki-laki ataupun perempuan yang tidak atau merasa terusik pada kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat Konsep ini menandai bahwa menjadi atau kehidupan janda-janda sering merupakan korban yang selalu dipersalahkan (blaming the victim), sebagai korban, mereka selalu dikonotasikan sebagai perempuan “genit” dan “binal”, sehingga dianggap sebagai salah satu warga masyarakat yang harus dikontrol, serta peran dan status mereka selalu berada pada posisi yang dimarginalkan di antara kelompok-kelompok perempuan lain, dan segala aktivitas 147 Kondisi peremuan (isteri) seperti ini dapat diibaratkan hanya mereka bermain di dalam lingkaran setan kehidupan yang tiada berakhir. Karena mereka (laki-laki) telah menggunakan struktur sosial (budaya, adat dan kemungkinan juga agama) setempat untuk melakukan pembenaran sebagai sarana yang ampuh untuk melakukan dominasi kepada para perempuan (isteri), yang walaupun mereka tetap penolak yaitu dengan melakukan ngerorot, sebagai bentuk resistensi terhadap transkrip publik atau formal 31 meskipun apa yang dilakukan oleh kaum perempuan (isteri) di dalam masyarakat suku Sasak masih bersifat lokal, spontan, dan sporadis. 5.KESIMPULAN Hasil studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tradisi Perceraian Studi ini menyimpulkan bahwa tradisi perceraian pada masyarakat suku Sasak dilakukan melalui pranata sosial yaitu ngerorot. Proses ini membentuk dua pola perceraian: (1), ngerorot nenangin diriq (ngerorot untuk menenangkan diri). Pola ini dipahami sebagai upaya dari seorang isteri untuk melakukan penarikan diri (withdrawing) pulang ke rumah orang tua secara sembunyi-sembunyi, yang merupakan tindakan simbolik yaitu meninggalkan situasi atau arena pertentangan baik secara fisik maupun psikologis untuk sementara waktu (temporarily), yang berfungsi untuk menghindari pertentangan yang lebih keras yang bisa membahayakan kedua belah pihak terutama isteri. Berguna untuk mengakhiri pertikaian sambil melakukan perenungan terhadap kekeliruan masing-masing, sehingga dapat melakukan menyesuaikan diri untuk menghadapi babak baru kehidupan rumah tangga.(2), pola ngerorotngerorot kemeleq seang (ngerorot ingin bercerai). Seorang melakukanya dapat menjadi simbol bahwa isteri karena tidak tahan lagi dengan kondisi kehidupan keluarga, dan ngerorot sebagai salah satu cara yang terbaik untuk melepaskan diri dari ikatan kontrak perkawinan yang tidak menyenangkan.Pada pola ini, bahwa pertentangan dan ngerorotnya isteri sudah mengarah pada terjadinya pembubaran perkawinan (cerai), di sini terjadi pertentangan yang keras, isteri tidak hanya melawan tetapi juga memberontak, sehingga di antara mereka tidak ada lagi kesamaan untuk terjadinya sebuah kompromi. Pola ini dipahami oleh mereka sebagai suatu tindakan simbolik dari seorang isteri yaitu meninggalkan arena pertentangan (rumah suami) ke rumah orang tuanya, baik secara fisik maupun psikogis untuk selama-lamanya (permanently). Tindakan ini berfungsi untuk meminta cerai kepada suaminya karena dengan meninggalkan arena pertentangan si suami dengan cepat dan langsung mengeluarkan kata-kata cerai yang kemungkinan sudah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh seorang isteri. 2. Perlawanan Perempuan mereka banyak yang tidak diperhitungkan ( Abdul Haris, Mobilitas Angkatan Kerja Wanita Indonesia ke Luar Negeri. Dalam Dalam buku “ Sangkan Paran Gender” , Irwan Abdullah (ed), 2003, hal, 177. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 31 Transkrip formal atau dapat juga disebut publik transkrip, yaitu semacam interaksi terbuka antara kelompok subordinat dan kelompok yang mensubordinasi, tidak hanya perkataan akan tetapi juga tindakan ataupun tingkah laku. Antonim dari taranskrip faormal adalah transkrip tersembunyi atau hiddin transcript, yang berarti tindakan, perkataan, maupun praktek yang dapat berupa gosif, desas-desus dan lain-lain. Pembahasan yang mendalam tentang hal ini dapat ditelusuri dari dasil penelitian Siti Kusujiarti yang berjudul: Antara Idiologi dan Transkrip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa. Dalam buku “ Sangkan Paran Gender” , Irwan Abdullah (ed), 2003, hal,89. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 148 Studi ini menemukan bahwa perlawanan perempuan terhadap suami di dalam ikatan perkawinan karena di dalam keluarga (hubungan suami-isteri) tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban moral yang mendasar dan tidak adanya distribusi yang adil terhadap sumber daya dalam keluarga. Seperti suami lari dari tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan, dan isteri dibiarkan sendiri untuk menanggung beban sendiri. Isteri tidak lagi memperoleh akan pengahargaan dari suami, dan suami tidak bisa menempatkan secara proporsional antara isteri sebagai teman, mitra dan kolega, dengan orang tua atau keluarga lain, yang sebenarnya bisa dipisahkan secara hitam-putih dari kehidupan sebagai sepasang suami-isteri. Beberapa faktor ini akan memicu terjadinya pertentangan dan ngerorotnya isteri. Selain itu bahwa perlawanan perempuan (isteri) dapat juga terjadi karenastruktur sosial yang ada di dalam masyarakat bertindak berlebihan sebagai a regulator agensi untuk melakukan regulasi terhadap tingkah laku perempuan (isteri), sehingga martabat mereka sangat tergantung dari adanya perijinan sosial atau a matter of social permission. Ngerorot yang dilakukan oleh perempuan (isteri) paling tidak untuk mensiasati dominasi dari laki-laki (suami), walaupun mereka tidak melakukan secara kelompok dan tidak pula digerakkan di dalam bingkai wadah tertentu yang dapat memberikan dan menimbulkan kesadaran pada perempuan-perempuan (isteri) yang lain yang tersubordinasi. 6.DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan (ed), 2003. Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Amin,dkk, 1997. Adat Istiada Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Eka Darma. Beauvoir De, Simone, 1999. SecondSex (terj). Pustaka Promethea Berger L, Peter, dan Thomas Luckmann, 1990. Tafsir Sosial Atas Kenyataan (terj). Jakarta: LP3ES. Berger L. Peter, 1994. Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial (terj). Jakarta: LP3ES Bhasin, Kamla, 1996. Menggugat Patriarki(terj). Yogyakarta: Bentang. Budiman,Arief, 1982.Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia. Camara, Helder Dom, 2000. Spiral Kekerasan (terj). Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar. Engineer, Ali, Asghar, 2000.Hak-hak Perempuan dalam Islam (terj). Yogyakarta: LSPPA. Fromm, Erich, 2000. Akar Kekerasan, Analisis Sosio-Psikologi atas Watak Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Goode, J, William, 1991. Sosiologi Keluarga (terj). Jakarta: Bina Aksara. Hendarti M, Ignatia,2000. “Kekerasan Simbolik: Protes Terselubung dalam Cerita Fiksi Populer Wanita indonesia”. Dalam Jurnal RENAI, Edisi oktober 2000-Maret 2001, tahun I, No. 1. Salatiga: Pustaka Percik. Hikam, A.S, Muh, 1999. “Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus”. Prisma, no, 8, thn XIX. Jakarta: LP3ES. Karin,Erna, 1999. “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”.T.O.Ihromi (peny), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Yakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mernissi, Fatima, 1999.,Peran Pemberontakan Wanita Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim(terj). Bandung: Mizan. Moore,L. Henrietta, 1998. Feminisme dan Antropologi (terj). Jakarta: Obor. Muhadjir, Noeng, 1989. Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik dan Phenomenologi. Yogyakarta: Rake sarasen. Nakamura, Hisako, 1990. Perceraian dalam Masyarakat Jawa. Yogyakarta: Gajah Mada press. 149 Jawad A, Haifaa, 2002. Otentisitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender (terj). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. Johnson P, Doyle, 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jilid 1 dan 2 (terj). Jakarta: Gramedia. Ramulyo, Idris M, 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Ritzer, G dan Douglas J, Goodman, 2004.Teori-Teori Sosiologi Modern (terj). Jakarta: Prenada Media. Saadawi, El Nawal, 2001. Perempuan dalam Budaya Patriarki (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Saxson, Lloyd, 1985. The Individual, Marriage, and the Family. California: Wadsworth Publishing Campany. Simon, Roger, 2000. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (terj). Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar. Syafruddin, Sumardi l dan Sukardi, 2009. Pengembangan Model Pendidikan keluarga Melalui kelompok Muslimat NW sebagau Upaya Mencegah terjadinya Perceraian Pada masyarakat Sasak Lombok. Mataram: laporan penelitian Lemlit Unrama Spradley, P.James, 1997. Metode Etnografi (terj).Yogyakarta: Tiara Wacana. Sushartami, Wiwik, 2002. “Perempuan Lanjang: Meretas Identitas di Luar Ikatan Perkawinan”. Dalam Jurnal Perempuan, Nomor 22, 2002. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Strauss, Amselm and Juliet Corbin, 1997. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, prosedur, Teknik, dan Teori Grounded (terj). Surabaya: Bina Ilmu. Vrendenbregt, J, 1981. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. 150 BERAS DAN GERAKAN SOLIDARITAS SOSIAL PEREMPUAN DALAM TRADISI NYAMBUNG DITENGAH MONETISASI PEDESAAN Dr. Soetji Lestari, M.Si.¹; Dr. Ign. Suksmadi Sutoyo, M.Si.²; Drs. Jarot Santoso, M.S.³; Drs. Tri Sugiarto, M.Si.⁴; Dr. Joko Santoso, M.Si.⁵; Drs. Nalfaridas Baharudin, M.Hum.⁶; Dra. Rin Rostikawati, M.Si.⁷ ¹Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto Email: [email protected], ²Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UniversitasJenderal Soedirman – Purwokerto, Email:[email protected] ³Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto Email:[email protected] ⁴Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto Email: [email protected] ⁵Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto Email: [email protected] ⁶Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto Email: [email protected], ⁷Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto, Email: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan nilai-nilai sosial ekonomi dalam beras; dan bertahannya beras sebagai media gerakan solidaritas sosial perempuan dalam tradisi nyumbang di tengah intensifnya monetisasi pedesaan.Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipetakan akar gerakan solidaritas sosial perempuan desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di pedesaan Jawa di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras masih menjadi bahan sumbangan yang utama bagi perempuan desa. Bagi perempuan desa, beras lebih memiliki nilai guna dan nilai tukar dibanding uang. Solidaritas sosial yang ditunjukkan melalui beras dalam tradisi nyumbang lebih merepresentasikan bagaimana prinsip-prinsip resiprositas harus ditegakkan mengingat ada mekanisme kontrolnya. Sebagai nilai guna, beras lebih bermakna daripada uang. Hal ini karena beras langsung berguna sebagai jamuan pokok tamu hajatan maupun untuk membayar jasa tenaga yang membantu acara hajatan. Sementara beras sebagai nilai tukar (ekonomi) lebih memiliki nilai kepastiandan memiliki nilai equivalensi yang ”tepat” sebagai alat resiprositassumbang-menyumbang; serta memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan cepat dibanding komoditas pangan untuk sumbangan yang lain. Fenomena ini memperlihatkan bahwa gerakan solidaritas sosial perempuan desamemiliki rasionalitas 151 sosial dan ekonomi secara bersamaan. Pertimbangan untung rugi secara sosial dan ekonomi sebagai dasar tindakan. Kata Kunci: Perempuan, Pedesaan, Solidaritas Sosial, Beras, Tradisi Nyumbang Abstract This study aims to identify and map the socio-economic values in rice; and the persistence of rice as a medium for women’s social solidarity movement in the tradition of gift giving amidst the intensification of rural monetization. From the results of this study are expected for mapping roots social solidarity movements among village women. The research method used a qualitative approach, took place in rural Java in Banyumas regency, Central Java province. The result showed that rice is still the main ingredient for donation by rural women. Rural women consider that the rice has a used value and exchange value than money. Social solidarity shown by the rice in a tradition representing how the principles of reciprocity must be upheld based on control mechanism. Rice is more meaningful than money because the rice use for dish of food offered the quests or to pay for services that help for celebration event. The rice has a precise and equivalence value for donation as social exchange tradition. The rise has high resale value and faster than donation of food commodities for others donation. This phenomenon shows that the rural women’s social solidarity movement based on both which social and economic rationality. Benefit considerations are socially and economically as a basis for action. Keywords:Women, Rural, Social Solidarity, Rice, Tradition Of Gift Giving 1.PENDAHULUAN Nyumbang (gift giving) dalam tradisi hajatan merupakan pranata sosial sekaligus simbol ikatan sosial masyarakat desa yang penting, yang memiliki fungsi resiprositas dengan cara saling memberi dan saling tolong menolong sekaligus menggambarkan dinamika interaksi komunitas warga desa.Nyumbang adalah konsep lokal Jawa yang merupakan konsep pemberian atau gift giving.Pada prinsipnya pemberian adalah konsep yang bersifat universal dalam berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia, sejak jaman kuno hingga jaman modern sekarang ini. Letak perbedaan ada pada objek pemberian yang bervariasi antar budaya dan antar waktu. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang diciptakan masyarakat yang menjadi media untuk saling memberi, saling menerima, dan saling membalas sehingga terjalin ikatan dan interaksi sosial antar warga masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim, bahwa faham tentang pertukaran yang sepadan untuk saling memberi, menerima dan membalas ini merupakan satu prinsip moral umum yang terdapat pada semua kebudayaan (Scott 1981). Dalam budaya Barat misalnya, dikenal dengan hadiah yang diberikan pada saat pernikahan, kelahiran, pemakaman, pesta ulang tahun, hari Natal,Santa Claus, Hari Valentine, Hari Ibu dan Hari Ayah, ujian, promosi jabatan, pindah rumah, menyambut atau pesta perpisahan. Orang juga memberikan sesuatu ketika diundang untuk makan dengan orang lain, atau ketika mengunjungi seorang teman yang sakit, memberi kepadapengemis, ke gereja, juga untuk amal (Komter 2007). Menurut Belshaw (1981) bahwa kesempatan untuk pemberian hadiah semakin meluas dan masih akan meluas lagi, seperti misalnya acara thanksgiving day (hari Selasa terakhir bulan November), Tahun Baru, Valentine Day (14 Februari), serta diperkirakan Halloween (31 Oktober)juga menjadi peristiwa sejenis. Sementara pada masyarakat kuno seperti di Samoa misalnya, sistem dari pemberianpemberian hadiah tidak hanya terbatas dalam hal perkawinan, tetapi juga muncul pada 152 peristiwa-peristiwa kelahiran bayi, sunatan, sakit, anak perempuan menginjak pubertas, upacara penguburan orang mati, dan perdagangan (Mauss 1992). Di Indonesia, peristiwa-peristiwa yang muncul dalam tradisi memberi hadiah (tradisi nyumbang) juga tidak jauh berbeda, hajatan yang bersifat suka (seperti perkawinan, khitanan, kelahiran, ulang tahun, dan lain sebagainya) dan peristiwa yang bersifat duka (kematian dan segala ritual yang mengiringi, sakit, dan musibah-musibah lainnya (Kutanegara, 2002; Lestari, 2010; Lestari, 2014). Peristiwa-peristiwa tersebut sangat bervariasi antar budaya dalam pelaksanaan tradisinya. Namun istilah tradisi nyumbang umumnya diidentikkan dengan kegiatan hajatan besar (perkawinan dan khitanan) yang melibatkan masyarakat (undangan/tamu) yang banyak dan istilah tersebut berkonotasi untuk masyarakat pedesaan. Di Madura, istilah tradisi nyumbang dikenal dengan nama de’nyande’, sementara di sebagian wilayah Jawa Timur ada istilah mbecek atau buwuh, jagongadalah istilah lain untuk tradisi nyumbang di Jawa Tengah, dan gantangan adalah istilah untuk tradisi nyumbang di Subang Jawa Barat (Prasetyo, 2012). Di masa lalu, nyumbang dalam sejarah masyarakat pedesaan yang masih didominasi oleh sistem ekonomi subsisten ditandai dengan hasil-hasil produk pertanian dan produk rumah tangga, termasuk juga hasil ternak seperti telor, daging ayam maupun daging sapi ataupun daging kambing, maupun hasil sayuran-sayuran dalam pekarangan rumah. Sementara produksi (industri) rumah tangga, khususnya yang dikerjakan oleh perempuan, adalah seperti jenang, jadah, criping pisang, dan lain sebagainya hampir semua bahan dasarnya sebagian besar merupakan produksi dari hasil pertanian sendiri. Banyak makanan-makanan khas buatan masyarakat desa yang dijumpai dalam tradisi nyumbang di pedesaan. Menurut Kutanegara (2002) tradisi nyumbang di pedesaan Jawa pada saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perubahan sosial ekonomi pedesaan telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan jenis benda yang disumbangkan. Pada saat perekonomian pedesaan didominasi oleh sistem ekonomi subsisten, yang diperkirakan terjadi sampai empat puluh tahun yang lalu (tahun 1970an), jenis-jenis barang yang disumbangkan untuk acara pernikahan atau supitan adalah bahan-bahan kebutuhan seperti beras, tiwul, kelapa, tempe, teh, gula dan sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi pasar, pengeluaran yang harus ditanggung rumah tangga desa ini semakin berat. Kalau sebelumnya nyumbang dapat menggunakan produk pertanian, namun sekarang lebih banyak menggunakan uang tunai. Dengan demikian setiap warga desa membutuhkan lebih banyak uang dalam rangka memenuhi kebutuhan di luar konsumsi harian, ini menyebabkan uang lebih penting dalam setiap transaksi sosial (Husken dan White 1989: Abdullah 1990; Darini 2011). Sistem ekonomi pasar (uang) yang ada juga ikut berpengaruh terhadap pranata-pranata sosial di pedesaan, termasuk dalam hal tradisi nyumbang. Pada saat ini masyarakat sudah terbiasa menyumbang uang untuk hajatan termasuk di wilayah-wilayah pedesaan. Namun di tengah monetisasi yang sangat intensif berlangsung di pedesaan, hasil penelitian yang dilakukan Lestari (1999; 2010, 2014, dan 2015) menunjukkan bahwa perempuan di wilayah pedesaan Kabupaten Banyumas masih bertahan dengan beras sebagai bentuk sumbangan utama pada kegiatan hajatan. Bukan hanya bertahan dalam bentuk berasnya, namun juga dalam hal besarannya yakni sekitar 2,5 kg beras. Solidaritas sosial yang ditunjukkan perempuan desa melalui sumbangan beras ini perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di pedesaan, terutama dari sistem ekonomi subsisten menuju sistem ekonomi pasar. Berbagai studi tentang tradisi nyumbang di pedesaan yang dilakukan oleh Hefner (1983), Djawahir (1999), Kutanegara (2002), Prasetiyo (2003), Lestari (2010; 2014), Prasetyo (2012), dan Sutoyo (2015) memperlihatkan bahwa beras merupakan media resiprositas yang penting dalam pranata 153 sosial tradisi nyumbang di pedesaan. Bentuk gotong royong dan solidaritas sosial dalam tradisi nyumbang ditunjukkan melalui sumbangan beras. Beras menjadi alat tukar sosial yang penting dalam transaksi sosial ekonomi pedesaan. Namun demikian studi-studi tersebut umumnya tidak memberikan porsi secara khusus bagaimana hubungan beras dan gender dalam tradisi nyumbang. Dalam tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan nilai-nilai sosial ekonomi dalam beras; dan bertahannya beras sebagai media gerakan solidaritas sosial perempuan dalam tradisi nyumbang di tengah intensifnya monetisasi pedesaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipetakan akar gerakan solidaritas sosial perempuan desa. 2.TINJAUAN PUSTAKA Altruism, giving, pro-social conduct, and reciprocity are the basis of the existence and performance of societies, through their various occurrences: in families; among the diverse motives of the political and public sectors; as the general respect and moral conduct which permit life in society and exchanges; for remedying “failures” of markets and organizations (which they sometimes also create); and in charity and specific organizations (Kolm, 2006) 1. Tradisi Nyumbang dalam Teori Pertukaran Sosial Salah satu dasar hubungan sosial kerjasama adalah gift giving ataupun saling tukar hadiahyang dipelihara melalui nilai-nilaialtruism, giving, pro-social conduct dan reciprocity. Molm (2010) mengidenfikasi pentingnya resiprositas antara lain dari: Hobhouse (1906) yang menyebut sistem resiprositas merupakan prinsip-prinsip yang penting dalam masyarakat, sementara menurut Simmel (1950) bahwa keseimbangan dan kohesi sosial tidak bisa ada tanpa ada sistem resiprositas, sedangkan menurut Becker manusia adalah spesies “homo reciprocus”. Menurut Belshaw (1981), untuk memahami sistem ekonomi suatu masyarakat yang mengkaitkan dengan analisa budaya dan sosial, maka tidak ada jalan lebih baik daripada memulainya dengan kelembagaan tukar-menukar. Sebagai lembaga tersendiri, tukar menukar telah menerobos seluruh bangunan sosial dan dapat dipandang sebagai tali pengikat masyarakat. Dari sini akan terlihat bagaimana sekelompok masyarakat saling tolong menolong, bergotong royong, saling memberi dan memanfaatkan berbagai jasa yang ada. Tradisi tukar menukar hadiah adalah tradisi yang bersifat universal, lintas bangsa, lintas etnis, juga lintas kelas. Tradisi tukar hadiah juga tumbuh subur di tengah masyarakat desa yang miskin sekalipun. Sudah sejak dalam masyarakat primitif kuno, relasi sosial dan interaksi antarwarga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain melalui sistem tukar menukar pemberian yang melibatkan kelompok-kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Proses saling memberi mengandung pengertian yang mengharuskan si penerima untuk melakukan pengembalian pemberian yang lebih dari apa yang diterimanya. Selain itu tradisi tukar menukar hadiah juga mencerminkan adanya persaingan dan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ini karena dalam pemberian juga ada motif-motif kompetisi, persaingan, pamer, dan keinginan untuk menjadi agung dan kaya. Solidaritas sosial dapat tercapai melalui proses-proses dinamik ini (Belshaw 1981; Mauss 1992; Komter 2005; Molm 2010). Dengan demikian sistem tukar-menukar hadiah ini merupakan penggerak terwujudnya dinamika dalam masyarakat karena dilandasi oleh prinsip persaingan dalam solidaritas yang menyeluruh (Mauss 1992), atau sebagaimana yang dikatakan oleh Kolm (2006) sistem tukar menukar merupakan basis keberadaan masyarakat. 154 Teori hadiah adalah teori solidaritas sosial dengan fokus utamanya adalah bagaimana cara ikatan sosial tetap bertahan dan terpelihara (Komter 2007; Molm 2010) yang juga menjadi ranah dari ketertiban sosial (istilah Parsons). Karena itu teori ini banyak menjadi ranah studi Antropologi dan Sosiologi. Tradisi pemikiran antropologi dan sosiologi mengenai hadiah dan resiprositas telah dilakukan oleh Mauss, Malinowski, Simmel, Sahlins, Gouldner dan Strauss (Komter 2005) maupun oleh Belshaw (1981). Sementara di satu sisi, tradisi sosiologi dalam mengembangkan teori solidaritas dan social order merupakan bagian kerja dari Durkheim, Weber dan Parsons. Namun demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Belshaw (1981) pikiran-pikiran ekonomi, antropologi dan sosiologi merupakan disiplin ilmu yang berada dalam satu sistem, termasuk oleh pemikir yang lebih awal, Durkheim, menurut Collins (1994) tidak memisahkan antara sosiologi dan antropologi. Selanjutnya bagaimana kemudian konsep pemberian ini dipahami dalam perspektif dalam sosiologi. Di sini yang perlu dipahami adalah bahwa warisan intelektual yang berpuncak pada teori-teori pertukaran modern sangat beragam. Teori pertukaran sosial selama ini ada dalam ranah keragaman disiplin ilmu. Warisan apa yang menggolongkan keragaman ini seringkali memiliki kaitan yang tidak jelas antara para ahli teori pertukaran kontemporer dengan para pendahulu mereka. Lagi pula, teori-teori pertukaran saat ini tampaknya merupakan percampuran yang tidak spesifik antara ekonomi utilitarian, antropologi fungsional, sosiologi, dan psikologi perilaku. Sebagai hasilnya, mengusut akar dari teori pertukaran, menurut Turner (1998), adalah suatu usaha yang berwawasan luas dan tidak pasti. Konsep resiprositas merupakan konsep sentral bagi teori pertukaran sosial, terutama sebagaimana yang dikembangkan oleh Homans dan Gouldner (Poloma 2000). Menurut Poloma yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada suatu teori tunggal tentang pertukaran sosial, melainkan ada beberapa teori berdasarkan fenomena-fenomena pengharapan timbal balik yang masing-masing berakar sangat dalam pada pada asumsiasumsi yang sedikit berbeda tentang hakikat manusia, masyarakat dan ilmu-ilmu sosial. Walaupun terdapat perbedaan dasar dalam pandangan, tetapi teori-teori pertukaran sosial juga memiliki beberapa asumsi yang sama mengenai hakekat interaksi sosial, yang utama dan paling sederhana adalah bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi: orang menyediakan atau memberikan barang atau jasa dan sebagai imbalannya juga berharap memperoleh barang atau jasa. Pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, dalam berbagai transaksi sosial yang dipertukarkan adalah hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Meskipun ada beragam teori pertukaran sosial, namun mengingat konsep tradisi nyumbang dalam penelitian ini banyak mengacu pada konsep pemberian (gift-giving) dari teori pertukaran sosial Mauss, maka mendasarkan pada pemetaan tradisi sosiologi dari Collins (1994), tradisi nyumbang merupakan tradisi Durkheimian. Apalagi selama ini tradisi nyumbang banyak dikaji dari sisi sosiologi dan antropologi sosial. Dalam pandangan Durkheim, tidak terdapat perbedaan yang berarti antara sosiologi dan antropologi sosial. Dalam hal ini terdapat dua sayap dari tradisi Durkheimian, yakni pandangan makro dan pandangan mikro (macroemphasis dan microemphasis). Yang dianggap sebagai ahli sosiologi makro adalah Montesqueiu, Comte dan Spencer. Sementara yang berada pada sayap mikro antara lain adalah keponakannya sendiri yaitu Mauss. Sayap yang berpandangan mikro yang lebih dekat dengan antropologi sosial, yang memberikan tekanan pada mekanisme ritual-ritual sosial kelompok yang menghasilkan solidaritas. Durkheim sendiri selain berada pada sayap mikro ketika mengemukakan teori ritual, juga berada pada sayap makro ketika mengemukakan teori pembagian kerja dan struktur sosial. Durkheim juga mencoba untuk merajut level makro dan mikro secara bersamaan melalui teori pertukaran dan mengembangkannya bersama Mauss dan Strauss. Dengan kata lain 155 teori jaringan pertukaran ritual adalah merupakan keterkaitan antara level makro dan mikro. Basis awal pertukaran sosial adalah konsep resiprositas yang muncul jauh sebelum masyarakat mengenal pasar uang, sehingga resiprositas juga ada berbagai tipe sejalan dengan perkembangan beragam karakter masyarakat. Menurut Sahlins (1972) terdapat tiga tipe relasi resiprokal yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama adalah generalized reciprocity (resiprositas umum) atau pertukaran yang dikenal sebagai pemberian secara umum tanpa harapan untuk mendapatkan balasan. Transaksi yang berlangsung dalam tipe ini dikenal berlandaskan semangat altruisme. Karenanya, dalam kategori pertukaran ini dapat dimasukkan berbagai relasi pertukaran seperti ‘pure gift’ (pemberian hadiah], 'sharing' (berbagi perasaan maupun material], 'hospitality' (keramah-tamahan seseorang kepada orang lain). Kategori atau tipe pertukaran kedua adalah balanced reciprocity (resiprositas sebanding) yang menunjuk pada kegiatan pertukaran secara langsung. Kategori pertukaran langsung tersebut setipe dengan mutual-reciprocal dalam konseptualisasi Levi-Strauss. Terjadi pertukaran yang seimbang antara dua pihak yang bertransaksi (tanpa delay) sebagaimana tampak pada 'paymet’' (pembayaran), 'buying and selling' (jual beli), ‘gift-exchange’ (tukar-menukar kado). Tipe pertukaran yang ketiga disebut sebagai negative reciprocitv (resiprositas negatif) yaitu sebuah upaya mengambil sesuatu (manfaat atau keuntungan) oleh pihak pertama yang (kemudian) menyisakan kerugian di pihak kedua yang telah memberikan sesuatu kepada pihak pertama. Dalam kategori pertukaran yang timpang ini adalah berbagai bentuk perampokan, perampasan (appropriation, fraud, stealing). Selain itu juga perjudian dan korupsi termasuk dalam kategori ini. Tipe pertukaran ekonomi yang terakhir ini seringkali bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai 'criminal economy' (Dharmawan 2007). Analisis Kutanegara (2002) mengenai pola sumbang-menyumbang di perdesaan Jawa menunjukkan adanya pergeseran dari generalized reciprocity menuju direct reciprocity yang sedang berlangsung secara intensif di masyarakat ini. Perubahan bentuk sumbangan dan cakupan wilayah sumbangan yang semakin menyempit menunjukkan bahwa proses transformasi sosial telah terjadi di perdesaan Jawa. Proses ini memang seiring dengan proses transformasi ekonomi yang terjadi sejak awal Orde Baru. Sebenamya trend penurunan intensitas timbal-balik sudah kelihatan cukup lama. Kartodirdjo (1987) menyatakan bahwa berbagai kegiatan resiprositas yang berkembang di perdesaan Jawa telah mengalami perubahan. Hal itu tampak dari semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan praktik gotong-royong dan berkurangnya jenis-jenis gotongroyong dalam masyarakat. Penyebab berkurangnya praktik gotong-royong adalah semakin besarnya pengaruh ekonomi uang ke perdesaan. Ketergantungan masyarakat dengan uang untuk memenuhi kebutuhan harian menyebabkan berbagai pertukaran jasa yang berkaitan dengan kegiatan produksi diselenggarakan dengan memakai alat tukar berupa uang. Gotong-royong yang masih hidup di desa adalah gotong-royong di luar kegiatan ekonomi, misalnya peristiwa penyelenggaraan pesta perkawinan, sunatan, dan upacara kematian. Sementara itu Molm (2010) memberikan perhatian bagaimana struktur dalam resiprositas. Walaupun Blau (1964) dan Simmel (1950) memberikan perhatian pada faktor struktur untuk teori-teori pertukaran, tetapi menurut Molm (2010) adalah Emerson (1972b) yang benar-benar merubah pendekatan teori pertukaran dari studi aktor beralih mempelajari bagaimana struktur mengatur pertukaran. Melalui studi struktur jaringan pertukaran, Emerson melakukan analisis dari level mikro ke makro. Dua dimensi dalam teori struktur jaringan Emerson adalah “kekuasaan” dan “ketergantungan” Emerson mendefinisikan “kekuasaan”sebagai “ongkos potensial yang ditujukan seorang aktor agar ‘diterima dan dibayar’ orang lain”, sedangkan “ketergantungan” adalah “ongkos potensial yang akan diterima dan dibayar seorang aktor dalam suatu hubungan” (Ritzer 2008). 156 Sementara menurut Molm (2010), struktur jaringan menggambarkan bagaimana aktor dan relasi-relasi pertukaran langsung terhubung satu sama lain. Struktur resiprositas menggambarkan bagaimana perilaku pertukaran aktor dan pertukaran manfaat terhubung satu sama lain. Ada dua kuncidimensi struktur yang mendasari dan membedakanberbagai bentuk pertukaran: pertama, apakahmanfaat dapat mengalir hanya secara sepihak atau bilateralantar aktor; kedua, apakah manfaat yang dibalas secara langsung atau tidak langsung. Keduanya dapat dibedakan antara tiga dimensi utamabentuk pertukaran sosial: pertukaran langsung yang dinegosiasi, pertukaran timbal balik langsung, dan tidak langsungatau pertukaran umum. Pemetaan yang dilakukan oleh Molm tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipetakan oleh Sahlins (1972) sebagaimana sudah disinggung di atas. Mengingat dalam direct reciprocity, barang atau jasa yang dipertukarkan sebanding, nilai pertukarannya cenderung bersifat kelompok-kelompok terikat oleh solidaritas sosial yang kuat sehingga merupakan satu unit yang utuh, karena itu nilai pertukarannya banyak bersifat simbolik (Molm 2007). Nilai-nilai ekspresif bisa dalam bentuk solidaritas sosial, kepercayaan, ikatan afektif yang semuanya bermanfaat dalam mengembangkan modal sosial. 2. Gender dan Pertukaran Sosial Dalam studi-studi antropologi klasik mengenai pemberian, perempuan digambarkan sebagai obyek pertukaran hadiah, bukan sebagai subjek atau aktor, sebagaimana yang digambarkan Strauss (Komter 2005). Ketidakjelasan perempuan sebagai aktor otonom dalam pertukaran hadiah sebagai tandahirarki dominasi pria atas perempuan. Menurut pendapat Marilyn Strathern (1988 ) dalam The Gender dan The Gift, bagaimanapun, interpretasi ini bias oleh prasangka Barat. Di Melanesia tidak ada hubungan permanen dominasi ada di antara pria dan perempuan. Sebaliknya, perempuandan laki-laki merupakan alternatif subjek atau objek untuk satu sama lain dalam upaya mereka untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dengan cara pertukaran hadiah. Peranan perempuan dalam pertukaran hadiah pada masyarakat Barat belum banyak menjadi fokus penelitian. Dari studi yang masih terbatas memerlihatkan bahwa perempuan merupakan pemberi yang lebih banyak dari laki-laki tetapi juga perempuan sebagai penerima yang lebih besar (Komter, 2005).Mengapa perempuan merupakan pemberi dan penerima terbesar? Padahal pada dasarnya seperti sudah diungkap di atas, perempuandan laki-laki merupakan alternatif subjek atau objek untuk satu sama lain dalam upaya mereka untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dengan cara pertukaran hadiah. Demikian pula motiv kasih sayang, rasa hormat, atau rasa terima kasih, juga manipulasi, menyanjung, atau perhatian pribadi merupakan motif yang umum untuk bisa memberikan yang tentu saja,ini berlaku untuk kedua jenis kelamin. Yang menjadi persoalan adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sumber daya yang berbeda. Dalam pemberian hadiah ini, perempuan terjebak dalam paradoks mendasar. Di satu sisi, pertukaran hadiah mereka dapat dianggap sebagai sarana yang kuat untuk menegaskan identitas sosial untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial. Di sisi lain, mengingat tidak setara kekuasaan mereka sosial dan ekonomi dibandingkan dengan pria, wanita menanggung risiko kehilangan identitas mereka sendiri dengan memberikan banyak kepada orang lain. Dalam tindakan memberi, perempuan secara bersamaan menciptakan kesempatan untuk menyimpan atau memperoleh kekuasaan, dan membuat diri mereka rentan terhadap hilangnya kekuasaan dan otonomi. Ide Weiner tentang "keeping-while-giving" - bertukar sesuatu untuk menjaga - adalah ilustrasi sempurna tentang ketegangan paradoks perempuan memberikan hadiah yakni untuk mengatasi ancaman kehilangan (otonomi), mereka memberikan hadiah secara berlimpah. Sebagai konsekuensi dari pemberian berlimpah 157 mereka menghadapi ancaman kehilangan otonomi mereka (Komter 2005). Perbedaan gender dalam pemberian hadiah menggambarkan peran penting perempuan dalam menciptakan semen sosial masyarakat. Meskipun banyak bentuk solidaritas, namun gender tidak sama sekali disentuh.Walaupun emansipasi mereka yang meningkat, perempuan masih memiliki pangsa terbesar dalam perawatan informal. Dalam kasus ini solidaritas adalah jelas berhubungan dengan gender. Dalam kerangka inilah pentingnya kajian gender dan pertukaran hadiah. Bagi perempuan desa, nyumbang penting untuk memelihara hubungan sosial sekaligus perlu strategi nafkah untuk memelihara hubungan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Gender adalah isu yang sentral dalam melihat strategi nafkah di perdesaan. Gender adalah bagian yang integral dan bagian yang tak terpisahkan dalam strategi nafkah di perdesaan. Hal ini karena laki-laki dan perempuan memiliki aset, akses dan kesempatan yang berbeda. Seperti misalnya perempuan jarang memiliki tanah sendiri (Ellis 1999). Namun demikian rendahnya akses perempuan ke bidang pertanian, justru membuka kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-farm. Pekerjaan ini bahkan dianggap menguntungkan bagi rumah tangga dan bagi perempuan itu sendiri. Pekerjaan pertanian sangat tergantung musim, sementara pekerjaan non-farm memberikan jaminan untuk kebutuhan sehari-hari walaupun jumlahnya relatif kecil, yang penting mereka memiliki uang tunai (Abdullah 2001). Implikasinya kebutuhan harian dan sosial menjadi tanggung jawab perempuan. Intensifikasi pertanian telah banyak menggiring perempuan ke sektor perdagangan, khususnya perdagangan kecil (informal). Meskipun terdapat pandangan yang negatif dari masyarakat Jawa terhadap profesi pedagang sebagai pandangan yang diwariskan oleh kalangan priyayi Jawa dan muncul sejak awal masuknya perdagangan dalam perekonomian Indonesia, khususnya ke Jawa, keterlibatan perempuan dalam dunia perdagangan di desa tidak terpengaruh oleh penilaian negatif tersebut (Abdullah 2001). Ini dimungkinkan dengan pertimbangan bahwa dengan berdagang, perempuan memiliki uang tunai yang lebih teratur dibanding profesi petani yang penghasilannya tergantung musim. Keteraturan perempuan dalam memiliki uang tunai menyebabkan banyak kebutuhan harian yang menjadi tanggung jawab perempuan, termasuk untuk kebutuhan nyumbang. Menurut Kutanegara (2002), tradisi nyumbang bagi rumah tangga miskin menjadi beban yang sangat memberatkan kehidupan mereka. Banyak aset rumah tangga seperti ternak dan barang-barang lainnya yang harus dijual untuk memenuhi kewajiban sosial ini. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka terpaksa hidup sangat sederhana. Perempuan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga adalah pihak yang paling merasakan beban berat tersebut. Hasil penelitian Djawahir (1999) menunjukkan bahwa dalam semua pranata nyumbang selalu melibatkan pihak perempuan, sementara laki-laki sangat terbatas keterlibatannya. Selama ini secara sosial budaya, posisi dan peranan perempuan ditempatkan pada bidang-bidang yang bersifat domestik (urusan rumah tangga) dan ekspresif (menjaga keharmonisan sosial), sebagaimana yang sudah dilabelkan oleh masyarakat. 3.METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan mengambil setting lokasi sub budaya Jawa Banyumasan (yang diwakili desa-desa di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah)Subyek penelitian adalah perempuan/ibu rumah tangga (miskin) dari berbagai latar belakang pekerjaan, terutama buruh pabrik bulu mata dan pekerja rumah tangga (PRT). Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dan observasi dengan terlibat dalam kegiatan tradisi nyumbang. 158 Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam menyebut istilah Banyumas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada empat (4) pengertian untuk istilah Banyumas, yakni sebagai eks karesidenan, sebagai wilayah administrasi Kabupaten, sebagai wilayah administrasi kecamatan dan sebagai salah satu sub budaya Jawa yang dikenal dengan istilah budaya Banyumasan. Dalam studi ini istilah Banyumas lebih mengacu pada istilah budaya, sebagai salah satu varian budaya atau sub budaya Jawa yang terletak di bagian barat kebudayaan Jawa; dan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu sampel lokasi penelitian. Keberadaan wilayah Banyumas yang terletak di belahan barat selatan Provinsi Jawa Tengah ini hidup dalam suasana dua budaya kuat, Sunda dan Jawa. Lokasi Banyumas yang jauh dari ibukota atau pusat kebudayaan Jawa (Keraton) menyebabkan masyarakat di daerah Banyumas memiliki keleluasaan mengekspresikan dalam budayanya yang khas. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan budaya Sunda di daerah perbatasan (Priyadi 2002). Istilah untuk keberadaan Banyumas yang jauh dari pusat kekuasaan (keraton) ini adalah adoh ratu, cedhak watu, yakni jauh dari keraton dan lebih dekat dengan batu atau alam pedesaan (Marwah, 2013). 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1. Peta Sosial Beras dalam Pranata Tradisi Nyumbang di Banyumas Dalam kultur masyarakat pedesaan di Banyumas, nyumbang dalam tradisi hajatan (khususnya perkawinan dan khitanan) adalah pranata resiprositas yang memiliki dimensi gender. Ini artinya ada pembagian kerja secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan dalam memberikan sumbangan, laki-laki menyumbang uang dan perempuan menyumbang bahan pangan. Sumbangan bahan pangan dari perempuan masih dapat dibedakan lagi yaitu: pertama beras saja; dan yang kedua adalah non beras dan beras atau tanpa beras. Beras adalah sumbangan perempuan dari masyarakat umum dalam lingkup satu desa, sedangkan sumbangan non beras(ditambah beras atau tanpa beras) berasal para tetangga dan kerabat dekat. Sejak dulu sampai sekarang besaran sumbangan beras yang berlaku umum dalam masyarakat desa Banyumas adalah 2,5 kg. Tempat sumbangan beras pun umumnya dalam bentuk yang sama, yakni tas plastik kotak. Untuk membedakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan tas ini, tas diberi nama pemiliknya. Bagi sebagian kalangan juga menilai bahwa pemberian nama pada tempat beras tersebut juga berfungsi sebagai legalitas sosial, bahwa seseorang telah diketahui dan diakui sudah ikut menyumbang (Lihat gambar 1). Tas ini juga dapat disebut sebagai tas resiprositas, karena setelah selesai menyumbang hajatan, pada saat pamit pulang tas ini akan diisi bingkisan balasan nyumbang. Hal ini mengacu pada teori resiprositas dari Mauss (1992), yakni bahwa terkandung tiga kewajiban dalam teori pertukaran dari Mauss. Pertama, memberi hadiah (nyumbang) sebagai langkah pertama menjalin hubungan sosial. Kedua, menerima hadiah bermakna sebagai penerimaan ikatan sosial. Ketiga, membalas dengan memberi hadiah dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan integritas sosial (Koentjaraningrat 1980). Besaran sumbangan beras 2-2,5 kg sebagai sumbangan yang berlaku umum dari warga desa perempuan di Banyumas ini relatif kecil dibanding sumbangan-sumbangan beras dari desa pada wilayah lain. Hasil penelitian Kutanegara (2002) di wilayah pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan sumbangan untuk tetangga dan kerabat jauh berkisar antara 5-7 kg beras, sedangkan untuk tetangga dan kerabat dekat sekitar 10-20 kg beras. Dalam masa krisis, naiknya harga berbagai kebutuhan pokok di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam ukuran besarnya sumbangan. Beras yang semula berharga sekitar Rp. 800 perkilogram telah naik menjadi Rp 2.500, sehingga jikalau 159 mereka tetap menyumbang beras, akan terasa memberatkan. Oleh karena itulah, pada masa krisis 1998 yang lalu bentuk sumbangan telah bergeser dari beras menjadi uang. Ketika terjadi pergeseran bentuk sumbangan, kriteria setempat (umume) menyepakati sumbangan kepada tetangga jauh dan kerabat jauh berkisar antara Rp. 10.000,00 – Rp 15.000,00, sedangkan untuk kerabat dekat antara Rp. 30.000,00 – Rp. 50.000,00, tergantung pada intensitas hubungan dan kondisi ekonomi mereka.Hal ini setidaknya memperlihatkan bahwa secara ekonomi, Banyumas memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah. Gambar 1. Tas NyumbangBeras : Tas Resiprositas (Tas Memberi Menerima dan Membalas) Khas Banyumas Dengan demikian diferensiasi sumbangan, yakni yang menyangkut jenis/bentuk, dan besar kecilnya sumbangan ditentukan oleh dua hal, yakni jenis kelamin dan ikatan kekerabatan. Sumbangan uang laki-laki bagi sebagian warga desa dianggap singgetatau simpel (sederhana), tidak pusing memikirkan jenis sumbangannya. Sementara untuk bahan sumbangan perempuan, terutama untuk tetangga dan kerabat dekat dianggap njlimet, karena tidak cukup hanya beras melainkan bahan-bahan pangan lainnya. Bukan hanya njlimet dalam memikirkan bentuk sumbangan, namun juga njlimet dalam mencari sumber penghasilan untuk nyumbang. Sistem hutang adalah hal biasa bagi perempuan desa. Bagi mereka lebih baik hutang daripada tidak hadir nyumbang. Uang dan beras memiliki nilaiyang berbeda bagi orang desa. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, beras jugabukan hanya sebagai bahan pangan pokok, melainkan keduanya telah menjadiinstrumen untuk menjamin keberlanjutan hubungan sosial di pedesaan. Uangdan beras yang dicatat dalam buku catatan gantangan adalah simbol yangmengikat hubungan antar individu maupun antar keluarga. Uang dan berastidak hanya dilihat dari jumlah dan nilainya, melainkan juga dilihat sebagaisebuah “komitmen moral” untuk saling membantu dan menepati janji satusama lain di pedesaan. Kesediaan menyimpan sejumlah uang dan beras tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan (trust) seseorang kepada orang lainnya.Kesediaan membayar kembali sejumlah uang dan beras yang pernahditerimanya juga menunjukkan tanggung jawab seseorang kepada warga (Prasetyo, 2012). 2. Bertahannya Sumbangan Beras dalam Monetisasi Desa Bentuk sumbangan desa pada awalnya memiliki nilai fungsional secara langsung untuk keperluan hajatan. Ketika dunia industri semakin berkembang bentuk sumbangan juga mulai berubah mengikuti ekonomi pasar, banyak makanan rumah tangga sudah tergantikan oleh produksi pasar. Demikian pula ketika sistem ekonomi uang telah 160 mendominasi kehidupan “pasar’ desa, nyumbang seperti transaksi ekonomi, ibarat orang membeli makan di sebuah warung makan. Ciri utama dari ekonomi pasar adalah penggunaan uang sebagai sarana transaksi dan orientasi tindakan ke arah profit dari para pelaku ekonomi (Nugroho 2001). Menurut Simmel (Blikololong 2010), pertukaran ekonomi merupakan bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan menyolok pada bentuk-bentuk interaksi antara para aktor sosial. Uang dapat dibagi-bagi dan dimanipulasi secara presis, dan memungkinkan pengukuran yang eksak untuk ekuivalennya. Uang bersifat impersonal, berbeda dengan benda-benda yang dibarter seperti gong dan kerang. Uang mendorong kalkulasi rasional dalam kehidupan manusia dan meningkatkan rasionalisasi yang menjadi ciri masyarakat modern. Manakala uang menjadi penghubung utama antarmanusia, ia menggantikan ikatan personal yang berakar dalam perasaan yang meluas dengan relasi impersonal yang mempunyai tujuan spesifik. Akibatnya, kalkulasi abstrak merasuk ke bidang-bidang kehidupan sosial seperti hubungan kekerabatan atau bidang estetika yang sebelumnya menjadi domain penilaian kualitatif. Dengan kata lain, uang adalah mesin utama yang meretas jalan dari Gemeinschaft ke Gesellschaft. Karena uang, spirit kalkulasi dan abstraksi modern mengalahkan pandangan dunia lama yang memberikan tempat utama bagi perasaan dan imajinasi. Dampak dari monetisasi juga terasa pada aspek sosial budaya. Penggunaan uang telah memudahkan orang untuk mengekspresikan rasa simpati, dan juga kontribusi sosial dalam pengertian jumlah dan menjadi lebih obyektif (Nugroho 2001). Pada awalnya simpati hanya bisa diartikulasikan dalam bentuk subyektif tetapi kemudian dengan monetisasi membawa pengaruh pada obyektifikasi ekspresi simpati. Beras sampai saat ini merupakan alat resiprositas yang vital dalam tradisi nyumbang di perdesaan Jawa.Di perdesaan Banyumas, sumbangan beras ini berlaku untuk semua aktifitas nyumbang kecuali untuk tilik bayi. Beras menggambarkan kebutuhan pokok masyarakat desa yang paling mendasar. Beras dengan demikian di samping sebagai kebutuhan pokok konsumsi masyarakat desa, juga berfungsi sebagai kebutuhan pokok bagi rumah tangga desa (perempuan) untuk nyumbang. Beras juga menjadi simbol sosial untuk menilai besar tidak sebuah hajatan yakni melalui banyaknya pengeluaran beras (karena banyak tamu) dan banyaknya sumbangan beras. Sebagaimana dikatakan oleh Kutanegara (2002), di wilayah desa Bantul DIY, ada tiga hal yang dipakai sebagai patokan untuk menilai besar kecilnya hajatan. Kriteria pertama adalah dengan mengukur jumlah beras yang dihabiskan. Semakin banyak beras yang dihabiskan, semakin besar acara itu. Kedua, cakupan dan banyaknya tamu yang datang. Bila tamunya banyak dan sebagian besar berasal dari luar wilayah, mereka menyebutnya hajatan besar. Ketiga adalah dengan melihat di pemilik acara apakah menerima atau tidak sumbangan dari tetangga atau orang lain. Jika ”nompo sumbangan”/menerima sumbangan, berarti hajatan itu termasuk besar. Demikian pula masyarakat Tengger Jawa Timur dalam mencatat nilai sumbangan juga disetarakan dengan nilai kilogram beras, yang kemudian hal ini dijadikan dasar untuk membalas besarnya sumbangan ke pihak penyumbang apabila kelak mengundang hajatan (Hefner, 1983). Selanjutnya di Subang Jawa Barat, pertukaran sosial di desa disebut dengan gantangan yang secara harafiah artinya adalah sebuah satuan ukur dengan nilai 1 gantang sama dengan 10 liter beras. Pada prakteknya gantangan adalah pertukaran beras dan uang yang dilakukan antar tetangga/kenalan kepada bapak hajat (penyelenggara hajatan) sebelum atau ketika pesta hajatan berlangsung yang bersifat sebagai simpanan tamu hajat yang kelak harus dikembalikan oleh bapak hajat (Prasetyo, 2012). Nilai gantangan tersebut minimal sebesar setengah gantang (5 liter). Dengan demikian beras merupakan media penting untuk sistem resiprositas bagi banyak masyarakat desa khususnya dalam tradisi 161 nyumbang. Atau dengan kata lain beras merupakan alat tukar yang berkeadilan bagi warga desa (perempuan) dibanding dengan uang. Di Banyumas, alasan lain penggunaan sumbangan beras adalah karena beras merupakan kebutuhan pangan pokok warga desa jadi beras selalu tersedia setiap saat. Hal ini terutama bagi para rumah tangga petani pemilik. Umumnya mereka memiliki persediaan beras baik itu untuk konsumsi sendiri maupun untuk keperluan nyumbang. Bahkan menurut penuturan warga, kebutuhan beras untuk nyumbang jauh lebih banyak dibanding untuk konsumsi pangan rumah tangga. Pada kenyataannya, saat ini tidak semua warga desa bisa menghasilkan beras sendiri. Kelompok ini jumlahnya jauh lebih besar. Sebagian besar subyek dalam penelitian ini bukan merupakan rumah tangga petani (pemilik). Banyak di antara mereka sebagai penerima bantuan raskin (beras miskin). Beras raskin ini banyak diburu oleh perempuan untuk nyumbang yang harganya lebih murah Rp. 1000 dibanding beras umumnya. Beras ini kemudian dikenal dengan nama beras sumbang, karena putarannya dari nyumbang ke nyumbang. Beras ini dibeli warga perempuan untuk nyumbang yang kemudian dijual kembali oleh pemilik hajatan ke warung dan dibeli lagi oleh warga untuk nyumbang, begitu seterusnya. Menurut penuturan warga kalau punya hajat pada tanggal muda, biasanya beras yang diterima sebagian besar merupakan beras sembako (raskin) karena pembagian raskin umumnya pada tanggal muda. Ada banyak kalkulasi/perhitungan sosial yang dipertimbangkan oleh perempuan untuk tidak beralih dari beras ke uang sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah. Perhitungan sosial perempuan ini didasarkan pada banyak aspek, antara realitas dan tuntutan ekonomi pasar (uang), norma serta kebutuhan akan eksistensi diri yang menyangkut pengakuan sosial. Kalau sebelumnya nyumbang dapat menggunakan produk pertanian, namun sekarang dengan sistem ekonomi pasar, nyumbang lebih banyak menggunakan uang tunai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laki-laki menyumbang uang secara langsung, sementara perempuan yang menyumbang bahan pangan tidak lagi dapat dipenuhi secara subsisten melainkan harus diperoleh melalui ekonomi pasar. Hal ini terutama perempuan dari rumah tangga miskin yang tidak lagi bekerja di sawah dan tidak memiliki lahan pertanian. Dengan demikian setiap warga desa membutuhkan lebih banyak uang dalam rangka memenuhi kebutuhan di luar konsumsi harian, ini menyebabkan uang lebih penting dalam setiap transaksi sosial (Husken dan White 1989: Abdullah 1990; Darini 2011). Perkembangan semacam ini menyebabkan ketergantungan orang desa terhadap uang semakin besar dan meluas. Ekonomi subsisten kehilangan kekuatan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal ini perempuan tampak sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi, karena secara sosial budaya, perempuan adalah pengatur ekonomi rumah tangga. Sementara dalam transaksi sosial seperti tradisi nyumbang, perempuan merupakan aktor sosial penting yang banyak mengambil peran (Geertz 1983; Stoller 1984; Abdullah 2001; Djawahir 1999; dan Lestari 2010 ). Keterbatasan uang tunai yang dimiliki perempuan menyebabkan ketergantungan mereka pada warung desa cukup tinggi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan untuk nyumbang, dan dilakukan dengan cara berhutuang. Mereka tidak selalu memiliki uang tunai, sehingga hutang membeli beras atau bahan sembako lainnya ke warung adalah lebih memungkinkan daripada hutang uang ke tetangga. Sebaliknya warung juga tidak akan laku kalau tidak dapat dihutangi. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan kalkulasi/perhitungan sosial perempuan desa yang tidak dari beras atau bahan sembako/bahan pangan lainnya ke uang yang didasarkan pada banyak aspek, antara realitas dan tuntutan ekonomi pasar (uang), norma serta kebutuhan akan eksistensi diri yang menyangkut pengakuan sosial. 162 Tabel 1 Kalkulasi Sosial Perempuan Desa untuk Tidak Beralih dari Beras ke Uang Dasar Rasionalitas/Kalkulasi Faktor Penyebab Keterangan Sosial Ekonomi 1. Kalkulasi Ekonomi 1. Barang sudah tersedia Daripada harus menjual (Rumah tangga petani beras, lebih baik langsung pemilik) menyumbang beras 2. Keterbatasan uang tunai Hutang beras ke warung yang dimiliki (rumah desa lebih memungkinkan tangga non petani) daripada hutang uang ke tetangga. Warung desa sulit laku apabila tidak menggunakan sistem hutang. Beras sebagai kebutuhan pokok relatif selalu tersedia 3. Memiliki alat tukar yang Nilai tukar uang lebih cepat lebih tepat dibanding uang berubah 4. Memiliki nilai jual kembali Dibanding jenis komoditas yang tinggi lain, beras memiliki nilai jual yang paling tinggi 5. Uang memiliki trust yang Beras disimpan dalam tas rendah dibanding beras sumbang sehingga legalitas sosialnya lebih terkontrol dibanding uang yang disimpan dalam amplob yang memungkinkan terjadinya manipulasi. Kalkulasi Sosial 1. Manfaat langsung Hidangan utama dalam hajatan di desa adalah makan besar (nasi). Beras juga berfungsi untuk membayar jasa tenaga yang rewang (perempuan) 2. Kebiasaan/tradisi Menurut sebagian perempuan mereka tidak mantap kalau tidak menjinjing tas. Dengan semakin bergesernya rumah tangga petani ke non petani, beras semakin mahal mereka jangkau, sementara nyumbang adalah kewajiban sosial yang tidak bisa mereka tinggalkan, sehingga beras sumbang atau beras raskin menjadi alat legalitas sosial yang sah untuk mewujudkan rasa solidaritas sosial mereka sebagai warga desa. Mereka para perempuan dari rumah tangga miskin rela berebut beras sumbang demi bisa ikut berpartisipasi dalam sistem resiprositas desa. 5.KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa beras masih menjadi bahan sumbangan yang utama bagi perempuan desa. Bagi perempuan desa, beras lebih memiliki nilai guna dan nilai tukar dibanding uang. Solidaritas sosial yang ditunjukkan 163 melalui beras dalam tradisi nyumbang lebih merepresentasikan bagaimana prinsip-prinsip resiprositas harus ditegakkan mengingat ada mekanisme kontrolnya. Sebagai nilai guna, beras lebih bermakna daripada uang. Hal ini karena beras langsung berguna sebagai jamuan pokok tamu hajatan maupun untuk membayar jasa tenaga yang membantu acara hajatan. Sementara beras sebagai nilai tukar (ekonomi) lebih memiliki nilai kepastian dan memiliki nilai equivalensi yang ”tepat” sebagai alat resiprositas sumbang-menyumbang; serta memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan cepat dibanding komoditas pangan untuk jenis sumbangan yang lain, sekalipun hal itu yang mereka gunakan adalah beras raskin, beras yang tidak layak konsumsi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa gerakan solidaritas sosial perempuan desa memiliki akar rasionalitas sosial dan ekonomi secara bersamaan, dimana pertimbangan untung rugi secara sosial dan ekonomi sebagai dasar tindakan. 6.DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan, 1990. ”Perempuan ke Pasar: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan” dalam Buletin Penelitian dan Kebijaksanaan Kependudukan POPULASI No. 1/Tahun 1990, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Abdullah, Irwan, 2001. Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang Press, Yogyakarta Abdullah, Irwan, 2001. ”Teori dan Praktik Komunalisme: Krisis Ekonomi, Sumber Daya Lokal dan Respon Sosial di Sriharjo, Yogyakarta” dalam Franz von BendaBeckman, Keebet von Benda-Beckman, Juliette Koning (Editor): Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Belshaw, Cyrill S., 1981. Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern, PT Gramedia, Jakarta. Blikololong, Jacobus Belida, 2010. Du-Hope di Tengah Penetrasi Uang – Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Sistem Barter di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, Disertasi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, Depok. Damsar, 1998. Sosiologi Ekonomi, Rajawali Pers, Jakarta. Damsar, 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Djawahir, Fatmah Siti, Soetji Lestari, Rawuh Edy Priyono, Edy Suyanto, 1999. Kajian Sosial Ekonomi dan Budaya Terhadap Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Mengenai Tradisi Nyumbang dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa-desa IDT di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas – Laporan Penelitian, FISIP-UNSOED, Purwokerto Hefner, R.W., 1983. The Problem of Preference: Economic and Ritual Change in Highlands Java, Man, New Series Vol. 18/4 Koentjaraningrat, 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Kolm, Serge-Christope and Jean Mercier Ythier (Ed.), 2006. Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Volume 1, Elsevier B.V. Komter, Aafke E., 2005. Social Solidarity and The Gift, Cambridge University Press, New York Komter, Aafke, 2007. “Gifts and Social Relations: The Mechanisms of Reciprocity” dalam jurnal International Sociology January 2007 Vo. 22 (1), International Sosiology Association – SAGE, London. Kusujiarti, Siti, 1997. “Antara Ideologi dan Transkip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa” dalam Irwan Abdullah, ed. Sangkan Paran 164 Gender, Pustaka Pelajar, Diterbitkan untuk Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kutanegara, Pande Made, 2002. ”Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan” Buletin Penelitian dan Kebijakaan Kependudukan POPULASI Volume 13 Nomor 2 Tahun 2002, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kutanegara, Pande Made, 2002. Sumbangan dan Solidaritas Sosial; Jerat Kultural Masyarakat Pedesaan Jawa, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta. Lestari, Soetji, dkk., 2010. Tradisi Nyumbang dan Feminisasi Kemiskinan (Mencari Pola ”Manajemen Nyumbang” yang Berbasis Lokal untuk Pemberdayaan Perempuan Desa), Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Lestari, Soetji, 2014. Posisi Perempuan dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa: Potret Dinamika Monetisasi Desa, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Marwah, Sofa. 2012. Representasi Politik Perempuan di Banyumas : Antara Kultur dan Realitas Politik (Studi di Lembaga Legislatif Empat Kabupaten Periode 20092014), Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Mauss, Marcel, 1992. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Nasikun, 1990. “Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan: Teori dan Implikasi” dalam Buletin Penelitian dan Kebijaksanaan Kependudukan POPULASI 1 (1), PPK UGM, Yogyakarta. Nugroho, Heru, 2001. Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Prasetiyo, Ari, 2003. Tradisi Nyumbang dalam Masyarakat Desa Tamantirto – Suatu Studi Tentang Sistem Pertukaran dalam Masyarakat Transisi – Tesis – Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, Depok. Prasetyo, Yanu Endar, 2012. Pertukaran Sosial di Pedesaan: Studi Kasus Komersialisasi Gantangan di Tiga Desa Miskin Subang - Tesis – Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Instititut Pertanian Bogor. GERAKAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU WANITA PRO LINGKUNGAN: KASUS KABUT ASAP Rizki Takriyanti 165 Rancangan Pengajian Gender, FSSS, University of Malaya Email:[email protected] Abstrak Isu pokok dalam penyelidikan ini adalah menganalisis bagaimana tingkahlaku wanita terhadap lingkungan dapat mewujudkan gerakan sosial di sebuah Kota. Penyelidikan ini adalah penyelidikan kualitatif dan metodenya kes studi feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan temubual mendalam dan pengamatan terlibat. Hasil penyelidikan menyimpulkan tiga perkara yakni hal-hal yang mendorong dan menjadi gerak kuasa (catalyst) praktis lingkungan tingkahlaku wanita adalah pengetahuan, motif dan sikap. Kedua tingkahlaku pro lingkungan wanita untuk mengatasi kabut asap, mereka menghemat pemakaian Bahan bakar Minyak (BBM) dan elektrik, menanam pohon, memilih rumah yang terdekat dengan kantot. Ketiga usaha yang dilakukan wanita untuk lingkungan yang berkelanjutan adalah mengubah cara pandang tentang memperlakukan lingkungan dan wanita sebagai objek yang tidak menganggu relasi dan peran laki-laki, wanita dan lingkungan, supaya tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan ketidakberdayaan wanita sehingga dari tingkah laku yang pro lingkungan akan menjadi sebuah gerakan sosial.Penyelidikan menyarankan agar semua pihak khususnya pemerintah perlu mengkaji kembali paradigma pembangunan yang demokratis dan transparansi berperspektif lingkungan sehingga memungkinkan kontrol penduduk dalam era otonomi ini sepatutnyalah ada ruang untuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Keywords: Gerakan, Sosial, Perilaku, Wanita, Lingkungan. Abstract Central issue in this research is to analyze how the womans behaviour towards the environment can realize a social movement in a city.This research is a qualitative investigation and case study methode feminimst. Data collection techniques and observation dept interview involeent. The results of the investigation concluded three cases of pushing and being practical power of the environmental movement behaviour of women is knowledge, motiver and attitudes.The second pro environmental behaviour of women to overcome the haze, to save onfuel oil and electrical, plant a tree, choose a house that is closet to office. The three efforts made by the woman for the environments and women as objects no longer interfere with relationship and roles of men, women and the environment. Hopefully no more damage to the environment and powerlessness of women. This study suggests that all parties, especially the government needs ro review the paradigm of development, of a the democratic and transparent royal perspective enabling environmental control society especially in the era of autonomy supposed to be a space for local knowledge in environmental management. Keywords: Social Movement, Behaviour, Women, Environmental 1.PENDAHULUAN Peran manusia terhadap pelestarian alam sekitar menjadi sangat strategik, karena selain manusia menjadi pengguna utama (main user), juga manusia sering di claim sebagai pihak yang paling tidak bertanggung jawab pada pelestarian lingkungan. Sebenarnya 166 lingkungan merupakan jantung kehidupan, kerana tanpa lingkungan sebenarnya manusia tidak boleh berbuat banyak; lebih tragis lagi manusia tidak bisa hidup. Lalu kenapa manusia menyalahgunakan peranan dan manfaat lingkungan tersebut? Hal ini terjadi kerana lingkungan dianggap sebagai sesuatu fenomena dan spektrum yang berjalan secara pelestarian, padahal banyak akibat yang sudah menjadi realiti sosial dan edukatif yang semestinya telah menjadi pelajaran bermakna bagi manusia dalam memaknai lingkungan sebagai ”keperluan hidup” manusia. Oleh karenanya perkara alam sekitar merupakan hal yang penting sejak beberapa dekade yang lampau. Pemanasan global dan perubahan iklim karena efek rumah kaca (green house effect), kerusakan tanaman, hutan, dan kepunahan species, berkurangnya sumberdaya ikan, lahan pertanian, polusi udara dan persediaan air adalah bencana utama bagi lingkungan di bumi (Oskamp, 2000). Awalnya permasalahan lingkungan disadari sebagai perkara teknis dan ekonomi. Sementara pada dekade terakhir dimensi sosial dan permasalahan lingkungan seperti perhatian publik dan sikap masyarakat terhadap lingkungan menjadi satu dari ranah sosiologi lingkungan dan psikologi lingkungan. Dalam hal ini tingkah laku lingkungan masyarakat dan tingkah laku ekologi dan akibat-akibat lingkungan telah diselidiki di negara maju dan negara berkembang selama beberapa dekade terakhir (Kalantari, Fami, Asadi, & Mohammad, 2007). Menurut Herbert Grossman dan Suzanne H.Grossman (1994) ketika generalisasi tentang perbedaan gender dapat menjadi misleading, adalah penting untuk mengenali bahawa beberapa perbedaan gender cut across kelas, etnis dan geografis terbatas, serta deskripsi kelas sosio-ekonomi atau kumpulan etnis cenderung menerapkan majoriti ahli mereka. Gender tidak muncul seketika, akan tetapi gender berkembang secara beraturan, masing-masing tahapan mempengaruhi pengembangan secara bertahap untuk membantu menghasilkan perbedaan gender yang kita lihat sebagai orang dewasa. Wanita merupakan salah satu major group kumpulan sumber manusia di masyarakat, yang mempunyai potensi besar sebagai kumpulan mandiri penunjang pembangunan. Kelompok wanita telah disepakati memiliki posisi yang sangat strategik dalam KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio Jeneiro, Brasil tahun 1992 yang menyepakati untuk melaksanakan agenda 21 sebagai dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ditindaklanjuti pada KTT Wanita di Beijing Tahun 1995 yang menghasilkan Deklarasi Beijing berisikan 12 CriticalAreas, diantaranya tindak penglibatan wanita dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya pada KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, masyarakat dunia menyepakati posisi penting dalam mencapai pola produksi dan konsumsi yang berwawasan lingkungan serta pendekatannya pada pengelolaan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan. Kesepakatan terhadap posisi strategik wanita pada berbagai forum Internasional dalam membuka peluang bagi penyelesaian masalah yang terkait antar wanita dan pembangunan berkelanjutan khususnya masalah lingkungan. Pembagian peranan wanita dalam kehidupan sosial seringkali menempatkan intensiti wanita lebih sering dengan lingkungan; yang menyebabkan wanita lebih peka dalam mengelola lingkungannya. Kemampuan organisasi wanita memungkinkan terbentuknya sesuatu "gerakan" yang mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang kurang sesuai. Karena itu, wanita mempunyai hak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai keterkaitan wanita dan lingkungan, sehingga peran, akses, dan pengawasan serta manfaat yang diterima kaum wanita dapat lebih maksimal (Bidang Pengembangan Kapasitas BAPEDAL Propinsi Jawa Timur, 2007). 167 Gerakan sosial wanita pro lingkungan adalah suatu proses tanpa akhir untuk mendukung dan mengembangkan mental, moral, etika, fisik, sikap dan tingkah laku agar menghasilkan insan yang mampu melestarikan fungsi lingkungan guna keberlangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lain yang ada di dalamnya. Menurut Lutfi Pratomo (http://beritahabitat.net/2008) wanita yang selama ini dilupakan oleh kaum lelaki dalam peran lingkungan sangat memprihatinkan. Sistem patriarkis selalu mendominasi dalam pergerakan dan kepedulian wanita terhadap lingkungan. Kebebasan wanita terbatas oleh kebijakan patriakis yang memberikan dampak kerusakan lingkungan yang fital. Ada kekeliruan dalam pendidikan yang selama ini di tanamkan oleh kebudayan di dunia. Otoriti lelaki sangat kuat memberikan impak terhadap wanita lebih tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya karena merasa takut bila diremehkan dan tidak didengarkan ideanya. Wanita lebih memilih diam karena takut akan represif yang di dominasi kaum lelaki. Mitos dan dogma memberikan punishmentbahwa wanita adalah makhluk yang lemah dan dididik menjadi makhluk emosi daripada rasio yang selama ini dikuasai oleh otoriti laki-laki. Sudah saatnya kita merubah paradigma yang sudah melekat bahawa wanita juga sudah boleh berdaya dan tidak lagi di bawah otoriti laki-laki dalam menyelamatkan lingkungan. Kerusakan lingkungan sa’at ini disebabkan tidak adanya rasa penghormatan terhadap ciptaan khususnya terhadap kaum wanita. Peradaban dunia menciptakan kekuasaan lakilaki dalam kehidupan yang sukar sekali menerima kritik. Rasionalitas dan biologis cenderung dibesar-besarkan menjadi peranan yang sangat dominan. Selain itu, rasionaliti lelaki membawa pengurangan rasa hormat terhadap bentuk sesuatu ciptaan. Kebudayaan tersebut semestinya kita tinggalkan bahwa pelestarian lingkungan seperti halnya wanita sebagai sesesuatu yang boleh dikawal dan dikuasai oleh otoriti lelaki. Menurut Henry Giroux (1992) gerakan yang lebih luas dalam teori feminis, poststrukturalisme, post-modernisme, studi kebudayaan, teori kesusasteraan (literary), dan dibidang seni adalah dialamatkan kepada isu pedagogi dalam politik perbedaan kebudayaan yang menawarkan harapan baru bagi sejumlah bidang yang mengalami kemunduran (for a deteriorating field). Dalam dunia tradisi religious dan kebudayaan, wanita sering dipikirkan dekat dengan pelestarian lingkungan, pelestarian lingkungan dilihat sebagai feminism, maka dunia pelestarian lingkungan disimbolkan sebagai wanita–Ibu. Selain itu pelestarian lingkungan sebagai wanita bijak yang mengatur segalanya. Akhirnya persepsi tentang pelestarian lingkungan mengalami perubahan sejarah. Pelestarian lingkungan lambat laun sudah tidak lagi dalam pemuliaan dan melampaui kebudayaan manusia. Pelestarian lingkungan lebih mudah boleh dikawal dan dieksploitasi tanpa batas seperti halnya otoriti lelaki yang mendominasi kaum wanita. Rasionaliti menciptakan hukumnya sendiri terbentuklah teknologi yang menguasai pelestarian lingkungan. Transendensi laki-laki didefenisikan sebagai lari dari pelestarian lingkungan dan perang terhadap realiti keibuan, realiti tubuh dan pelestarian lingkungan, semua yang membatasi dan menahan lebih dari yang dikawal laki-laki. Dengan cara inilah, melalui ilmu pengetahuan, pemikiran laki-laki memaksakan transendensinya atas pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan tidak lagi menjadi tubuh yang organik namun menjadi mesin yang dibentuk dan dijalankan dengan alasan yang suci. Hal inilah yang menyebabkan kerakusan ada ditangan lelaki. Apa yang kita alami sebagai makhluk yang semestinya menghormati ciptaanNya kini di batasi oleh alasan rasionaliti dan dogma agama yang selama ini kita hanya taken for granted. Diskriminasi terhadap wanita yang dilakukan laki-laki hanya membentuk sesuatu kebudayaan kekuasaan rasionaliti tanpa batas memberikan impak terhadap krisis lingkungan yang terjadi sa’at ini. 168 Ilmu pengetahuan dan feminisme menurut Ruth Hubbard, Mary Sue Henefin, dan Barbara Fried adalah, “Sebuah konstruksi manusia muncul kerana sebuah kondisi sejarah tertentu ketika dominasi laki-laki atas pelestarian lingungan masih terlihat sebagai sesuatu yang baik dan perlu di perjuangkan. Wanita sudah sering menyedari, lebih daripada laki-laki, bahawa kita adalah bahagian dari alam dan nasibnya ada ditangan manusia yang sering tidak peduli”. Hanne Strong mengatakan bahawa kunci untuk memperbaiki bumi terletak pada penghormatan terhadap hukum alam yang dipahami oleh masyarakat asli dan tradisional. Karena itu, masyarakat ini berbincang dengan kumpulan instruksi yang asli yang diberikan kepada mereka oleh Sang Pencipta. Sementara itu, perjuangan wanita Jambi melalui wakil rakyat, perjuangan anti pornografi, pelecehan seksual, ilegal logging, dan sejumlah kasus lainnya, merupakan sebahagian kecil perjuangan wanita di Kota Jambi. Perjuangan ini terasakan masih sangat kecil bila dibandingkan dengan perjuangan wanita masa dahulu. Alternatif penggantinya perjuangan ini dirasakan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan peranan wanita di kampung-kampung yang langsung bersentuhan dengan hutan. Wanita Jambi yang bertempat tinggal di wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi sejak dahulu hingga kini menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka sangat menyadari lingkungan (hutan) menjadi sumber kehidupan, baik dari aspek sosio budaya religius maupun aspek ekonomi. Dahulu bangsa Indonesia punya Kartini sebagai wanita yang memperjuangkan dunia pendidikan. Kini ada Butet Saur Marlina (Warung Informasi Konservasi Jambi), Emmy Hafild (Wahana Lingkungan Hidup) dan masih banyak lagi kaum wanita yang semakin peduli dengan lingkungan. Semua ini merupakan cerminan wahana representasi kemunculan wanita di masanya untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya dengan penekanan yang berbeda terhadap lingkungannya. Sekarang kita semakin sadar bahawa kerusakan lingkungan adalah akibat dari kerakusan yang hampir semua didominasi lelaki yang tidak memperdulikan kebebasan wanita untuk berucap dan berekpresi terhadap bumi dan makhluk hidup lainnya. Seperti yang diungkapkan Dale Spender “Ketika kedua jenis kelamin menggambarkan pengalamanpengalaman mereka sendiri dan ketika kedua versi itu dapat hidup bersama tanpa terbagi menjadi lebih unggul dan kalah, benar atau salah, aturan atau pelanggar, maka sebahagian dari mekanisme penindasan terhadap wanita telah dibuang”. Atau seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ”Dunia ini cukup untuk menghidupi semua orang yang ada di dalamnya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan segelintir orang”. Perkaranya, kenyataan menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara langsung berimpak terhadap wanita. Revolusi Hijau misalnya, pertama kali, meminggirkan wanita. Revolusi Hijau memaksa penggunaan bibit varieti unggul, sehingga pekerjaan perawatan dan pemilihan bibit yang tadinya dikuasai oleh wanita, kini tersingkir. Dan pemaksaan jenis tanaman tertentu dalam sektor pertanian, secara drastis telah menggusur wanita dari proses produksi pertanian, karena pengetahuan wanita atas keanekaan jenis tanaman tidak lagi dihargai. Ditambah mekanisasi secara intensif di sektor pertanian, mengabaikan eksistensi petani wanita, kerana tidak diperkirakan kapasitas, kemampuan dan struktur tubuh wanita. Penggunaan mesin huller, menyingkirkan penggunaan ani-ani (finger knife)yang biasa digunakan wanita,tergantikan oleh sabit yang lebih berat sehingga wanita kehilangan atau bertambah beban pekerjaannya. Wanita pedesaan tersingkir dari pertanian ketika peralatan moden diperkenalkan dan diasosiasikan dengan peran laki-laki. Sementara akses wanita pada pengambilan keputusan di sektor pertanian tetap tidak ada. 169 Ancaman lain adalah pekerjaan yang bersentuhan dengan pestisida, dimana wanita, yang paling lama terpapar pestisida karena beban kerjanya di lapangan pertanian, maupun ketika mereka bekerja di lingkungan rumah tangga, seperti membersih, karena beberapa jenis pestisida menetap dalam air. Ibu mengandung beserta janinnya paling rentan terhadap kimia beracun seperti DDT, endrin, dsb, yang mengakibatkan resiko penyakit kanker, terganggunya perkembangan janin, metabolisme, maupun jaringan otak. Tentu saja impak ini tidak terlihat secara langsung dalam hitungan hari atau bulan, melainkan boleh dalam hitungan tahun. Siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap resiko-resiko ini? Perkawinan usia dini sebagai ciri kebudayaan masyarakat agraris, mendorong angka kematian ibu yang tinggi, rendahnya pengetahuan reproduksi dan seksualitas wanita pedesaan, mengukuhkan peran wanita sebagai ‘pelayan seksual’ dan ‘penanggungjawab pemberi keturunan’ saat melakukan hubungan seksual, pelecehan seksual yang dialami buruh tani wanita, stigma ‘mandul’ bagi wanita yang belum mengandung, kekerasan dan ‘beban’ alat kontrasepsi terhadap wanita, gagal KB, aborsi, dan lain sebagainya (Sri Hadipranoto, Heru Santoso:2001). Kondisi ini kini semakin diperberat dengan berkurangnya subsidi pemerintah pada sektor kesihatan. Guna bertahan hidup, kebanyakan wanita pedesaan kemudian menjadi buruh tani dengan beban kerja berlebih, upah minimum, dan resiko kerja tinggi. Jika di desa tidak tersedia lagi pekerjaan, wanita terdesak mencari alternatif penghasilan dalam sektor-sektor yang tidak terlindungi dan eksploitatif, dengan bermigrasi. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kantung-kantung kemiskinan di daerah agraria juga menjadi kantung-kantung daerah asal buruh migran, pekerja seks, dan pekerja sektor informal kota. Ini menjadi katalisator untuk bermigrasi agar dapat bekerja di luar negara, seringkali melalui saluran yang tidak resmi. Jumlah wanita yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan meningkat tajam dalam dekade terakhir (feminisasi migrasi). Wanita pedesaan umumnya terjerembab menjadi korban perdagangan wanita dan anak (women and children trafficking). Selain itu, dalam berbagai konflik tanah dimana rakyat berhadap-hadapan dengan pengusaha (TNCs/MNCs) dan pemerintah, wanita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, seperti penggerayangan dan penelanjangan tubuh wanita, seperti yang terjadi di Bulukumba-Sulawesi-Indonesia baru-baru ini. Peristiwa Bulukumba, hingga kini masih meninggalkan trauma para wanita dan ibu-ibu masyarakat adat Kajang, atas kekerasan yang menimpa mereka. Hilangnya lingkungan hutan menyebabkan musnahnya tradisi lokal, di mana wanita umumnya mempunyai kepakaran khusus. Untuk wanita Dayak di KalimantanIndonesia juga bagi wanita adat (indigenous women) di belahan Indonesia lainnya-mereka mempunyai pengetahuan untuk mengenal plasma nutfah dan tahu bagaimana menjaga dan memeliharanya. Pertanian adalah daerah kekuatan dan kearifan wanita adat. Di Jambi misalnya kaum wanita dari kelompok “orang rimba” bukan hanya sekedar sebagai penerus keturunan saja, tetapi merupakan simbol kekuatan adat rimba yang sangat berperan dalam menjaga keharmonian alam sebagai tempat hidup mereka. Wanita suku Dani di Papua misalnya dapat mengenalkan 70 jenis ubi-ubian, dan wanita Moi di Sulawesi Tengah mampu mengenal 40 jenis tanaman obat, dan bagaimana cara menggunakannya untuk pengobatan. Jika komuniti lokal kehilangan teritori adatnya, pengetahuan dari kaum wanita di atas menjadi tidak bererti. Pengetahuan wanita di bidang pertanian kenyataannya mempengaruhi kualitas makanan dan ketersediaan pangan. Namun, kepakaran ini sama sekali tidak dihargai. Kebudayaan, tradisi dan model pembangunan yang tidak sensitif gender telah membentuk banyak wanita menjadi pribadi yang pasif, ”nrimo”, pantang bersuara dan tidak percaya diri. Jika kondisi ini terus dipertahankan (status quo) maka akan terjadi bencana kemanusiaan yang lebih buruk dari kondisi sa’at ini. 170 Pembangunan industri berbasis sumber daya alam semula jadi seperti industri perkayuan dan pertambangan, alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, mengakibatkan hilangnya area lahan bagi masyarakat adat. Wanita adat kehilangan sumber penghidupannya, perlindungannya dan kepercayaan diri dalam skala masif. Mereka dipaksa untuk menerima pekerjaan apapun untuk kelangsungan hidup mereka. Di Jambi misalnya, wanita ”orang rimba” yang ratusan tahun hidup di dalam rimba dan terproteksi dari dunia luar, sa’at ini terpaksa harus keluar dari dalam rimba agar dapat mendapatkan sumber makanan dari orang kampung. Bagi wanita ”orang rimba” berada di luar hutan adalah ancaman bagi keberlangsungan generasinya, karena tidak memiliki kapasitas untuk dapat cepat beradaptasi dengan dunia luar. Maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit dan HPH di Jambi telah memarginalisasi wanita terhadap hutan. Lebih parah lagi telah merusak peradaban dan kearifan wanita terhadap kelestarian lingkungan kerana mereka harus bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dan HPH yang sangat ekspolitatif terhadap lingkungan. Hal yang sama juga terjadi di kawasan lain seperti di Kalimantan banyak wanita Dayak terjejaskan dalam ‘kawin kontrak’ di mana mereka ‘menikah’ dengan para pekerja di industri perkayuan dan diterlantarkan segera setelah kontrak pekerja itu selesai dengan perusahaan. Anak-anak yang dilahirkan dari kawin-kontrak ini sering disebut sebagai ‘anak Asean’ di kampung mereka, menandakan para pekerja yang menjadi bapaknya berasal dari berbagai daerah di Asean, terutama Filipina dan Malaysia. 1. 1. Tempat Kajian Kawasan pengambilan data dalam penyelidikan ini adalah di Kota Jambi. Kota Jambi terletak di bahagian Barat cekungan Sumatera Selatan negara Republik Indonesia yang disebut Sub Cekungan Jambi yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur, kerana itu topografinya bercirikan dataran. Rajah 1: Peta Bandar Jambi Sumber:DDA Bandar Jambi, 2009 Visi pemerintah Jambi dalam pengendalian impak lingkungan di Kota Jambi dan harapan yang akan diwujudkan pada masa depan adalah ”terwujudnya Kota Jambi yang teduh dengan pembangunan lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”. 171 Tentunya makna yang terkandung dalam visi tersebut iaitu mewujudkan pelestarian lingkungan dalam suatu penataan wilayah yang serasi, selaras dan seimbang melalui aktivitas pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan lingkungan dengan melibatkan peranserta masyarakat baik laki-laki maupun wanita yang berkeadilan dan berkesinambungan. Kesepakatan nasional tentang pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) pada 21hb Januari 2004 di Yogyakarta telah ditetapkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan yang saling terkait dan saling menunjang iaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Menurut “World Bank Country Study” ancaman yang paling besar di kawasan perkotaan di Indonesia termasuk Kota Jambi adalah: a. Air yang tidak bersih untuk diminum langsung sebagai salah satu sumber utama penyakit, b. Pembuangan limbah yang belum memenuhi baku mutu ke media atau ke badanbadan air, c. Pengelolaan sampah yang kurang memadai (penumpukan secara tidak terkendali, pembuangan ke dalam sungai dan pembakaran), d. Pelepasan zat-zat pencemar udara oleh kendaraan bermotor karena gas kendaraan bermotor mengandung debu/jelaga dan timah hitam (timbal) (Pemerintah Kota Jambi, 2008). 1. 2. Isu lingkungan Kota Jambi Isu-isu lingkungan yang ada dan berkembang di Kota Jambi sa’at ini adalah: 1. 2. 1. Banjir/takungan air Pada beberapa tahun terakhir ini, salah satu permasalahan utama lingkungan di Kota Jambi adalah terjadinya genangan air maupun banjir di beberapa kawasan. Hal ini timbul kerana: - Merupakan Kota yang berada di dataran rendah dan dialiri Sungai Batanghari dan 9 (sembilan) sungai-sungai kecil serta 13 (tiga belas) anak sungai, - Pengaruh debit air sungai yang meningkat akibat hujan di daerah hulu/hilir sungai, - Perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai, - Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan pembuangan sampah yang tidak tertib, - Topografi struktur tanah dan vegetasi yang kurang baik, - Drainase yang kurang dan belum berfungsi secara baik. 1. 2. 2. Pencemarandan kerosakan alam sekitar 172 Isu yang tidak kalah pentingnya yang sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan Kota Jambi serta jumlah penduduk yang semakin bertambah, yang juga menjadi masalah di kota-kota lainnya adalah pencemaran dan kerusakan alam sekitar yang secara rincinya adalah sebagai berikut: 1.2. 2. 1. Penurunan kualitas air Penurunan kualitas air sungai sebahagian besar diakibatkan oleh semakin banyaknya jenis usaha dan/atau aktivitas yang membuang air limbah baik langsung maupun tidak langsung ke sungai maupun anak sungai dalam Kota Jambi. Disamping kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk memeriksakan air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke media yang dapat mencemari lingkungan. 1. 2. 2. 2. Penurunan kualitas udara Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini kualiti udara di Kota Jambi cenderung menurun. Perkembangan kawasan Kota Jambi yang semakin pesat seiring dengan keberadaan Kota Jambi sebagai pusat Provinsi dan menjadi pusat bisnis Provinsi Jambi menyebabkan semakin tingginya minat penduduk untuk datang, berkunjung dan bertempat tinggal sementara di Kota Jambi. Hal ini menyebabkan semakin tingginya tingkat kepemilikan kenderaan bermotor yang berimpak pada tingginya penggunaan kenderaan bermotor di jalan. 1. 2. 2. 3. Persampahan Pesatnya pertumbuhan penduduk telah menimbulkan masalah limbah padat khususnya sampah di Kota Jambi. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah timbul dikarenakan: - Volume sampah tidak tertampung di TPS dan kurangnya jumlah TPS, - Kurangnya sarana prasarana alat pengangkut sampah, - Rendahnya kesadaran masyarakat, - Lahan TPA sudah hampir penuh, - Penolakan masyarakat terhadap penempatan TPS, - Belum memiliki master plan persampahan Kota dan strategi pengelolaannya. Selama ini pengelolaan sampah dikelola oleh Pejabat Pengelola Kebersihan dan Pemakaman, yang mana pengerjaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga (CV. Usaha Sehat Bersama) pada lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan kontrak. (Kerajaan bandar Jambi, 2008). 1. 2. 3. Lahan kosong dan alih fungsi lahan Adanya lahan kosong dan alih fungsi lahan adalah isu lingkungan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini dikarenakan: 173 Perubahan fungsi lahan yang semula dari tanah kosong dijadikan lokasi perumahan dan lain-lain, Pembukaan lahan dengan cara pembakaran di pingir-pinggir kota, Praktek pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah/aktivitas pertanian yang tidak terkendali, 1. 3. Kerangka Konsep Wanita memiliki keterkaitan yang erat dengan alam sekitar. Dalam peranannya sebagai suri rumah, mereka lebih banyak berinteraksi dengan alam sekitar dan sumber daya alam. Impak kerosakan alam sekitarpun lebih sering dirasakan oleh wanita. 1. 3. 1. Tingkah laku pro alam sekitar wanita Merujuk pada pendapat Pieters, Bijmolt, Van Kaarj dan de Kruijk (1998) bahwa banyak individu mengatakan bahwa dirinya environmentalis, namun mereka tidak menterjemahkan sikap mereka tersebut kedalam tingkah laku pro lingkungan. Satu alasan barangkali bahawa pilihan antar bertindak dalam sebuah cara pro alam sekitar dan tidak mengerjakannya begitu kerap melibatkan sebuah konflik antara kepentingan individu yang segera dengan kepentingan kolektif jangka panjang. Keuntungan individu yang diperolehi dari perjalanan menggunakan kereta, membeli makanan dan produk lainnya tanpa pertimbangan impak negatif alam sekitar, tidak mendaur ulang dan tidak berjimat energi dalam rumahtangga adalah kepentingan segera, sementara impak negatif alam sekitar seperti tingkah laku tersebut di atas menyebabkan situasi tidak menentu dimasa hadapan (Nurdlund dan Garvill, 2002). Vlek & Michon (1992) Garvill, Laitila & Brydsten (1994) dan Nordlund & Garvill (1999) mengatakan bahawa melakukan perjalanan dengan kereta lebih berjimat masa dan lebih mudah serta menyenangkan, tetapi memiliki impak negatif yang banyak terhadap alam sekitar seperti kerosakan udara, kebisingan, dan konsumsi yang tinggi terhadap energi yang tidak terbarukan. Pada beberapa studi pemilik kereta merasa bahawa kereta lebih baik dan lebih unggul berbanding bas atau basikal bila dikaitkan dengan kepentingan individu tetapi berakibat burok bila dikaitkan dengan impak alam sekitar. Mereka juga merasa bahawa manfaat untuk individu lebih penting daripada manfaat untuk orang ramai (Nordlund, 2002). Beberapa ahli alam sekitar seperti Vining & Ebreo (1990), Mc Carty & Shrum (1994), Werner & Mkela (1998) serta Ebreo, Hersley & Vining (1999), menyebutkan bahawa kitar semula sampah adalah wujud penting dari pentadbiran sampah padat tetapi seringkali orang mengatakan sampah adalah sesuatu yang kotor dan memakan masa untuk mengelolanya. Oleh kerana itu mereka berat untuk melakukannya (Nordlund, 2000). Sedangkan Vining & Ebreo (1990) dan Mc. Carty & Shrum (1994)mengatakan bahawa kitar semula memerlukan upaya seseorang dalam menyortir sampah rumahtangga dan mengangkutnya ke beberapa sarana kitar semula. Kitar semula bagaimanapun memiliki impak positif terhadap alam sekitar dan impak sosial positif jangka panjang seperti penjimatan sumberdaya dan suatu upaya menolak penggunaan barang dalam pentadbiran sampah (Nordlund, 2000). Terbentuknya gas rumah kaca juga disebabkan oleh penggunaan energi. Penduduk di belahan bumi yang mengalami empat musim mengkonsumsi energi untuk memanaskan rumah mereka dan penggunaan elektrik lainnya untuk keperluan rumahtangga. Sebaliknya di negeri tropis pemakaian Air Condition (AC) telah menyedot banyak energi elektrik. Pendingin ruangan di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta misalnya menyedot elektrik paling banyak iaitu rata-rata 60 peratus dari total pemakaian elektrik (Kompas, 2008). 174 Beberapa kebiasaan sosial yang lebih maju dan menjadi bahagian dari tingkah laku pro alam sekitar ini berdasarkan saiz yang dibuat Nordland dan Jorgen Garvill (2002) terdiri dari empat bahagian dan duapuluh lima item, iaitu: 1. Tingkah laku yang ditunjukan dalam domain yang berbeza, seperti kitar semula plastik, kertas, metal; 2. konsumsi yang bertanggungjawab secara alam sekitar, seperti membeli produk-produk ramah alam sekitar; 3. penjimatan energi, seperti kebiasaan menjimat air panas; 4. Tingkah laku transportasi, seperti menggunakan angkutan awam daripada kereta pribadi. Untuk kondisi di Indonesia, item-item tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat di kota tertentu. Selain itu menurut Schultz and associates (2001), responden ditanyai tentang berapa sering melakukan 8 tingkah laku spesifik setahun terakhir, iaitu: 1. menggunakan kembali barangan bekas pakai (reuse); 2. mengolah kembali akhbar; 3. membeli produkproduk dalam kemasan-kemasan yang dapat digunakan kembali atau diolah kembali; 4. mengolah tin atau botol; 5. mendorong teman-teman/keluarga untuk mengolah barangan bekas pakai; 6. memungut sampah yang bukan anda hasilkan; 7. mengkomposkan sisa-sisa makanan; 8. menjimat bahan bakar dengan berjalan kaki atau menggunakan basikal. United Nation Development Program (UNDP) juga mengajukan 21 panduan hidup berkelanjutan yang berhubungkait dengan tingkah laku pro alam sekitar buku yang berjudul ”the geneva guide to sustainable living” (lampiran 1). Mengubah suai pendapat Nordlund dan Jorgen Garvill, Schultz and Associates dan UNDP dapat dikatakan bahawa tingkah laku pro alam sekitar (proenvironmental) adalah tindakan seseorang terhadap alam sekitar yang berkaitan dengan tingkah laku upaya memanfaatkan kembali barang bekas, kitar semula sampah/limbah, mencegah terjadinya sampah/limbah, konsumsi yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, upaya konservasi energi, serta tingkah laku transportasi yang cenderung bebas emisi udara. 1. 3. 2. Motif alam sekitar Dalam hubungannya dengan nilai moral dan motif alam sekitar, Stren dan Dietz (1994) telah menyajikan sebuah teori asas nilai concern alam sekitar dengan mengembangkan teori Schwartz (1977) tentang model norma aktivasi altruisme. Mereka berpendapat bahawa norma moral alam sekitar dapat diaktivasi melalui nilai-nilai sosio altruistik dan juga nilai-nilai biospheric dan egoistic. Mereka menyajikan sebuah klasifikasi tripartite orientasi nilai terhadap concern alam sekitar. ”Tiga orientasi nilai yang berbeza, terhadap diri sendiri, makhluk lain dan biospheric dapat dibezakan, dan bahawa masing-masing dengan bebas mempengaruhi tujuan-tujuan untuk bertindak secara politis dalam memelihara alam sekitar (Stern, Dietz, Kalof & Guagano, 1995). Secara khusus Schultz (2001) mengunakan 12 item sikap spesifik concern alam sekitar yang meliputi Environmental Motive Scale (EMS) untuk menguji tripartite. Dua belas objek yang dinilai ini meliputi concern terhadap tumbuh-tumbuhan, kehidupan laut, burung-burung dan binatang (biospheric), saya, gaya hidup saya, kesihatan saya dan masa hadapan saya (egoistic), dan orang-orang di negara saya, semua orang, budak kecil dan generasi masa hadapan (altruistic). Oleh kerana itu yang dimaksud dengan motif alam sekitar dalam penyelidikan ini adalah tiga orientasi nilai yang ada pada diri seorang wanita terhadap alam sekitar yang terdiri dari orientasi nilai terhadap diri sendiri, terhadap tumbuhan dan haiwan serta terhadap manusia lainnya. 1. 3. 3. Sikap pro alam sekitar Ada banyak teori dan pendekatan empiris untuk menyelidiki sikap terhadap alam sekitar dan literatur yang terkait. Sebahagian besar studi yang terkait dengan soalan ini 175 telah ada sejak 1970 dan seterusnya ketika konseptualisasi sikap alam sekitar sebagai sebuah konsep penyelidikan ilmiah yang mendapat perhatian khusus oleh penyelidik (Dunlap, 1998). Dimensionaliti adalah satu dari faktor paling kritis dari studi sikap alam sekitar. Penyelidik-penyelidik terdahulu melihat sikap alam sekitar sebagai konsep unidimensi. Kemudian banyak studi mengexplore multi dimensi sikap alam sekitar. Albrecht (1992) mengunakan faktor analisis dan menemukan tiga dimensi: keseimbangan alam (balance of nature), batas-batas pertumbuhan (limits of growth) dan manusia di atas alam sekitar (man over nature). Cluck (1997) mengambil data yang lebih luas di USA dan mengonsep sikap alam sekitar sebagai sebuah konsep tiga dimensi, yang meliputi ”environmental worldview”, environmental concern” dan ”environmental commitment”. Environmental worldview menyajikan bentuk umum dan dasar environmentalisme responden. Dari huraian di atas, sikap pro alam sekitar yang dimaksud dalam penyelidikan ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh pandangan yang baik terhadap alam sekitar, memiliki optimisme terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, tidak keberatan dikenai tarif yang lebih tinggi guna alam sekitar dan memiliki pandangan positif terhadap tindakan kerajaan terhadap alam sekitar. 1. 3. 4. Pengetahuan alam sekitar Ada beberapa studi yang menyebutkan bahawa pengetahuan (knowledge) memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungkait tingkah laku dan sikap alam sekitar dengan memberikan sokongan untuk meningkatkan pandangan dan argumen yang mendukung kepercayaan dan tingkah laku mereka terhadap alam sekitar (McFarlanc & Boxall, 2003). Miller (1990) meneliti tingkat pengetahuan alam sekitar bagi orang dewasa di Amerika. Miller melakukan survey dengan menginvestigasi pengertian awam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di USA. Satu komponen studi menguji pengetahuan awam tentang hujan asam dan lapisan ozon. Hasilnya menunjukkan bahawa hanya seperempat orang Amerika yang memiliki pengetahuan minimal tentang hujan asam dan lapisan ozon. Pada tahun 2004, sebuah survey lain dilakukan oleh the Kentucky Environmental Education Center (KEEC) yang mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan tingkah laku alam sekitar. Survey ini ingin melihat apakah warga Kentucky dapat menjawab beberapa pertanyaan yang sangat mendasar tentang isu-isu yang berkaitan dengan kualiti air dan lahan. Survey ini juga ingin mengetahui sikap warga tentang isu alam sekitar, seperti bagaimana sikap mereka dalam menjaga sumberdaya alam. Kemudian warga diminta untuk mengidentifikasi tingkah laku yang dapat memperbaiki alam sekitar. Kesimpulan umum dari hasil survey tersebut adalah bahawa walaupun masyarakat mengerti fakta-fakta ilmiah isu alam sekitar, namun pengetahuan tersebut tidak terkait dengan tingkah laku mereka terhadap alam sekitar. Dari huraian terdahulu maka penyelidik memberi batasan pengertian pengetahuan alam sekitar dalam kajian ini iaitu tingkat pemahaman yang dimiliki individu wanita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2. 1.Penyelidikan Terdahulu Hasil penyelidikan terdahulu tentang wanita dan alam sekitar yang diambil dari beberapa journal seperti journal yang bertajuk Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran (2007) yang mengangkat hipotesa sebagai berikut: (1). Umur, tingkat pendapatan, jabatan, pengajian dan pengetahuan lingkungan memiliki impak signifikan terhadap sikap dan 176 tingkah laku lingkungan; (2). Terdapat perbedaan signifikan antara tingkah laku laki-laki dan wanita dalam hubungannya dengan sikap lingkungan; (3). Sikap penduduk terhadap lingkungan, perasaan terhadap lingkungan (feeling of environmental), kesigapan/kesiapan penduduk bertindak dan aturan lingkungan memiliki impak signifikan terhadap tingkah laku lingkungan penduduk kota. Kesimpulan dari journal di atas tersebut merumuskan bahawa (1). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara lelaki dan wanita dalam sikap lingkungan, kesigapan/kesiapan untuk bertindak dan feeling of environmental. Wanita menekankan bahwa aturan lingkungan yang ada cukup untuk proteksi lingkungan dan jika aturan disempurnakan maka perkara lingkungan dapat dipecahkan. Tapi sebahagian besar lakilaki percaya bahawa aturan ini tidak cukup kuat dan seharusnya pemerintah membuat lagi aturan undang-undang untuk membuat penduduk dan bisnes terbiasa untuk melindungi lingkungan; (2). Terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan wanita dalam hal tingkah laku lingkungan. Wanita secara umum lebih concern lingkungan daripada lakilaki. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh penyelidikan Caiazza dan Barret; (3). Feeling of stress antara penduduk di Utara Tehran lebih tinggi daripada di Pusat dan Selatan. Karena perasaan ini, kesigapan untuk bertindak bagi konservasi lingkungan penduduk di Utara Tehran juga lebih tinggi. Kesimpulan ini juga berlaku dalam kasus top manager dan spesialis dibandingkan dengan pekerja; (4). Dari hasil analisis path dalam mengukur sikap dan tingkah laku, yang paling kuat bagi tingkahlaku lingkungan berasal dari tingkat pendapatan, kesigapan untuk bertindak dan sikap lingkungan. Feeling of stress, aturan lingkungan dan sikap lingkungan juga mempengaruhi tingkah laku lingkungan melalui kesigapan untuk bertindak. Pengaruh umur juga ditunjukkan oleh koefisien path tentang hubungan ini. Hubungan-hubungan tersebut dibuktikan dengan sejumlah studi yang dilakukan oleh Hines et al, Vogel, Bamberg, Buttel dan Taylor dan EORG, (5). Pendidikan dan pengetahuan berbasis perkara memiliki impak tidak langsung terhadap tingkah laku lingkungan. Pendidikan dan penguatan pengetahuan berbasis problem penduduk Tehran dapat mengubah sikap lingkungan dan akan meningkatkan feeling of stress masyarakat ke arah lingkungan. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya memperbaiki kesigapan untuk bertindak secara bersahabat dengan lingkungan khususnya dengan membantu aturan lingkungan. Semua ini dapat mengubah tingkah laku untuk memelihara lingkungan. Selain itu jurnal yang bertajuk A cross cultural study of environmental motive and their implications for proenvironmental behavior (2006) tidak menguji hipotesis khusus terhadap perbedaan budaya spesifik. Tapi lebih melihat (a). Bagaimana invarians pengukuran skala motif alam sekitar (EMS); (b). Bagaimana perbedaan cara-cara yang tampak dan tersembunyi dalam cocern biosfer, egoistic dan altruistic lintas kelompok; (c). Bagaimana hubungan concern motif lingkungan ini dan tingkah laku pro lingkungan yang timbul dari diri sendiri. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Kuesioner diedarkan kepada 658 mahasiswa (451 wanita, 207 laki-laki) dengan cakupan umur 16 hingga 66 tahun. Komposisi etnik sampel adalah 474 orang Selandia Baru asal Eropa dan 184 orang Selandia Baru asal Asia. Kesimpulan journal mengambarkan bahwa model tripartie concern lingkungan memberikan kesesuaian baik sampel orang Selandia Baru asal Eropa dan orang Selandia Baru asal Asia (2).Penyelidikan ini juga konsisten dengan temuan terdahulu di 20 negara tentang model tripartite Schultz (2001); (3). Bagi orangorang Selandia Baru asal Eropa dan Asia menilai dengan cara berbeza untuk item-item EMS dan kepentingan sama untuk masing-masing 3 item yang telah disebutkan. (4). Skor faktor egoistic orang Selandia Baru asal Asia secara signifikan lebih tinggi dari orang Selandia Baru asal Eropa, sebaliknya dalam concern biosfer skor Eropa lebih tinggi dari Asia, dan juga disebutkan bahawa orang Selandia Baru asal Eropa menilai persoalan 177 lingkungan lebih besar atas dasar biaya atau manfaat untuk ekosistem, sebaliknya Asia menilai persoalan lingkungan lebih pada dasar pribadi (egoistic). Bagi Selandia Baru asal Eropa, concern biosfer secara positif memperkirakan tingkah laku pro lingkungan, sebaliknya concern egoistic memperkirakan secara negatif; (5).Bagi Selandia Baru asal Asia sebaliknya, concern biosfer dan altruistic memprediksikan positif tingkah laku pro lingkungan. Ini juga bererti individu-individu dengan concern biofer lebih tinggi, bebas dalam tradisi budaya mereka, memperlihatkan tingkah laku lingkungan yang lebih bertanggungjawab. Bagaimanapun peran concern untuk diri sendiri (egoistic) dan concern untuk yang lain (altruistic) dapat membedakan lintas negara dalam meramalkan tingkah laku lingkungan; (6). Ada indikasi perbedaan-perbedaan etnokultural sistematik dalam concern motif lingkungan dalam hubungannya pada tingkah laku. Perbedaan ini menyarankan implikasi-implikasi bagi perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi lingkungan. Studi yang dilakukan para ahli di luar negara ini kebanyakan dilakukan di negara industri atau negara maju, dan belum pernah ada yang menyelidik tentang hubungkaitnya dengan kota kecil di sebuah negara berkembang yang menjadi lokasi penyelidikan. Posisi wanita yang selalu masih dipinggirkan di sebahagian besar belahan dunia mungkin sama dengan yang dialami oleh bumi. Perlakuan yang kurang baik terhadap wanita merupakan gambaran bahawa baik bumi mahupun wanita mendapatkan perlakuan yang kurang baik sehingga mengakibatkan kerosakan dan penindasan. Di bumi, pembangunan yang dijalankan cenderung tidak memperhatikan faktor keberlangsungan persekitaran yang baik. Sebagai akibatnya, kerosakan persekitaran yang terjadi semakin hari semakin parah. Meskipun mendapat perlakuan yang hampir sama, wanita harus diikutsertakan dalam menjaga persekitaran. Hal ini perlu agar wanita memahami betapa pentingnya persekitaran sehingga wanita akan menjaga dan memelihara persekitaran. Dengan pemahaman tersebut, wanita akan mempunyai peranan besar untuk menjaga dan memelihara persekitaran dengan baik dan juga dapat menjaga kebersihan persekitaran dari cakupan yang paling kecil. Menurut Dietz, Stern and Kalof (1993), ada bukti substansial bagi perbezaan gender dalam kepedulian persekitaran pada tingkat individu (Kalantari, 2007), dan ini mungkin diterjemahkan kedalam sebuah hubungan antara stratifikasi gender dan polisi persekitaran kerajaan bangsa. Selain itu dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Lee dan Norris (2000) menyebutkan bahawa terdapat perbezaan signifikan antara lelaki dan wanita dalam hal tingkah laku persekitaran. Wanita secara umum lebih concern 2. 2. Kerangka Teori Giddens (1981) menyatakan bahawa modeniti adalah kultur beresiko. Ini bukan bererti kehidupan sosial kini lebih berbahaya dari dahulu. Bagi kebanyakan orang itu bukan menjadi perkara. Konsep risiko menjadi perkara mendasar baik dalam cara menempatkan aktor yang berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Modeniti mengurangi risiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tetapi pada masa yang bersamaan memperkenalkan parameter risiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya (Ritzer, 2007). Kemudian Barry (2007) membagi resiko kedalam 4 (empat) kategori, iaitu: risiko-risiko ekologi, risiko-risiko kesihatan, risikorisiko ekonomi dan risiko-risiko sosial. Pada risiko ekologi akan ditemukan pemanasan global, kehilangan keanekaragaman hayati, penipisan lapisan ozon dan kerosakan ekosistem; Apa yang terjadi di dunia pada masa ini seperti terjadinya dampak pemanasan gobal yang luar biasa persis seperti apa yang dikatakan Ulrich Beck(1992); Sebagaimana 178 modenisasi melarutkan struktur masyarakat feodal abad 19 dan menciptakan penduduk industri, modenisasi kini melarutkan penduduk industri dan melahirkan tipe modeniti lain. Dalam buku ini Beckmenyampaikan tesis: kita kini menyaksikan bukan akhir, tetapi awal dari moderniti iaitu moderniti di luar rencana penduduk industri klasik (Ritzer, 2007). Tidaklah mengherankan bila contoh kehidupan moden masa ini menyebabkan risiko seperti yang dikatakan Barry. Seseorang menggunakan kereta untuk bekerja atau bepergian dengan alasan masa, jarak, keamanan dan keselesaan. Namun disisi lain pengendara kereta ikut memberi kontribusi bagi emisi udara gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan menimbulkan impak ikutan berupa empat kategori resiko. Kemudian begitu ramainya penduduk moden yang tergantung akan pemakaian elektrik, plastik, AC, kendaraan bermotor dan penggunaan bahan serta material yang sukar dihancurkan oleh tanah. 2.2. 1. Masyarakat perkotaan Dalam memahami bagaimana sebuah bandar berfungsi menjadi sangat penting dalam sosiologi di abad kedua puluh, Mazhab Chicago khususnya Robert Park (18641944) mendominiasi studi perbandaran. Park mengembangkan apa yang disebutnya pendekatan ekologis, yang ertinya adalah bandar menyesuaikan dirinya dengan cara yang teratur sebagaimana proses-proses ekologi alam sekitar. Bandar terlihat seperti mekanisme pengurutan dan penggeseran dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami, menyeleksi penduduk secara keseluruhan individu-individu yang cocok untuk tinggal dalam kawasan dan alam sekitar tertentu. Mazhab Chicago berminat besar pada interaksionisme simbolis yang berurusan dengan makna yang dilekatkan individu pada alam sekitarnya. Dengan kata lain, persoalan identiti dan sosialisasi atau bagaimana orang mempelajari tamaddunnya dan memproduksinya. Mengamati tingkah laku pro alam sekitar masyarakat (proenvironmental behavior) dalam paradigma keteraturan dari segi ontologis dan epistemologis adalah melihat realiti secara objektif, kerana menuntut adanya independensi dengan subjek yang diamati. Paradigma ini berakar pada positivisme Auguste Comte (1798-1857) yang mengedepankan bahawa pengetahuan manusia (human knowledge) harus berasal dari pengalaman inderawi dan empiris, dapat diamati (observable), dan dapat diukur (measurable). Oleh kerana itu melihat hubungkait antara masyarakat perbandaran dan tingkah laku pro alam sekitar mengutamakan kuantifikasi terhadap gejala-gejala sosial. Implikasinya dalam melihat hubungkait tersebut menekankan pada angka, hipotesis dan hubungkait kausaliti. Dihubungkan dengan tingkah laku masyarakat perbandaran terhadap alam sekitar adalah juga menganalogkan tingkah laku masyarakat yang pro alam sekitar dan tingkah laku yang tidak bersahabat dengan alam sekitar atau tingkah laku menyimpang. Menurut Merton (1938), tingkah laku menyimpang adalah hasil dari disorganisasi struktural yang terjadi pada level penduduk. Merton mengeksplorasi hubungkait antara tujuan-tujuan kultural dan cara-cara struktural untuk memperoleh tujuan-tujuan tersebut. Sementara bila cara-cara untuk mencapainya terhad untuk beberapa orang sahaja maka akan menciptakan tingkah laku menyimpang yang meluas. Jadi menurut Merton, tingkah laku menyimpang tidak terkait dengan kepribadian, tapi peran respon terhadap bentuk-bentuk kondisi yang universal dengan ketersediaan cara untuk mencapainya. Ketika penduduk tidak lagi mengikuti kesesuaian antara norma-norma dan tujuan-tujuan tamaddun maka terjadilah apa yang disebut dengan anomie (Merton, 1968). Anomie akan menciptakan tingkah laku menyimpang (deviance) dimana seseorang menggunakan segala cara, terkadang ilegal untuk mencapai kesuksesan materi (Ritzer, 1996). 179 Tingkah laku penyalur obat-obat terlarang atau pelacur yang melakukan pekerjaaan tersebut guna mencapai kesuksesan ekonomi dan menyebutnya sebagai tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh ketidakbertautan antara nilai tamaddun dan caracara struktur sosial mencapai nilai tamaddun itu. Inilah satu cara yang ditempuh fungsionalis struktural dalam upaya untuk menjelaskan tingkah laku menyimpang dan tindak kejahatan (Ritzer, 2003). Dalam hubungkaitnya dengan tingkah laku pro lingkungan, tingkah laku menyimpang dapat dianalogikan sebagai seseorang yang membuang emisi gas kendaraan ke ruang umum juga adalah menyebarkan racun. Demikian pula orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, merokok di tempat awam, mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa berpikir panjang untuk generasi depan, mengunakan produk teknologi yang boros bahan bakar, tingkah laku praktis tanpa memperhatikan pentingnya cara menggunakan kembali (reuse), kitar semula (recycle)produk dalam kemasan, mencemari alam sekitar dengan buangan sisa pepejal yang merugikan orang lain sekitarnya. 2. 2. 2. Habitus dan alam sekitar Menurut Sosiolog Perancis, Bourdieu (1994), tingkah laku perorangan yang juga dilakukan ramai orang disebut dengan kebiasaan sosial atau habitus. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyedari dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektika habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial (Ritzer, 2007). Jika habitus dihubungkan dengan alam sekitar, sebagai kebiasaan, tingkah laku itu berlangsung berulang dengan spontan sebagai salah satu cirinya, namun dalam proses pembentukan kebiasaan itu pada awalnya perlu ada sarana bantu untuk mengingat sehingga kebiasaan sosial itu akan muncul menjadi tindakan yang spontan. Contoh sederhana tingkah laku pro alam sekitar wanita yang dapat menjadi kebiasaan sosial adalah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, atau tingkah laku yang lebih baik lagi, iaitu menggunakan kembali (reuse), menolak pemakaian (reduce) dan kitar semula (recycle) barang-barang kemasan. Memburuknya kualiti alam sekitar suatu bandar atau daerah sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan alam sekitar di bandar atau daerah tersebut. Contoh yang baik dalam pengelolaan alam sekitar dapat dicontoh di Minamata-Jepang dan Curitiba-Brazil. Di Minamata-Jepang sebelumnya akibat yang diderita penduduk selain impak alam sekitar secara fisik juga putusnya ikatan sosial. Sedangkan di Curitiba-Brazil diawali dari sebuah kota metropolitan yang tumbuh dengan sangat pesat. Curitiba-Brazil menghadapi perkara yang tidak berbeza dengan bandar-bandar di negara berkembang yang kumuh, macetnya lalu lintas, menggunungnya sampah, banjir dan pembusukan alam sekitar. Namun sejak tahun 1971 arsitek Jarvine Lermer menjadi walikota dan dibantu perencana bandar yang cukup visioner Jonas Rabinovitch dan Jonas Leitmaef maka terjadi perubahan yang cukup drastis. Ini di sokong oleh filosofi sederhana iaitu ”inovasi bersama masyarakat, merancang bersahabat dengan alam dan memanfaatkan teknologi tepat guna”. Selain polisi kerajaan, gerakan sosial dipandang perlu untuk menggerakan penduduk untuk peduli alam sekitar. Dimana gerakan sosial selalu terarah kepada perubahan sosial dan berjuang untuk kepentingan alam sekitar, namun tidak sedikit pula yang memiliki motif lain seperti unsur wang dan politik. Sebab berdasarkan teori, kesempatan politik dan hubungan-hubungan kekuatan politik memelihara kemunculan strategi dan tenaga gerak bagi gerakan sosial (Tarrow, 1989). 180 Untuk terciptanya kualiti alam sekitar yang lebih baik perlu disokong oleh dua hal iaitu kebiasaan sosial masyarakat dan kebersihan fisik ruang awam melalui programprogram kerajaan. Kebiasaan sosial masyarakat dapat tercipta apabila masyarakat sudah memiliki tingkah laku pro alam sekitar. Kebiasaan mereka membuang dan mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, konsumsi energi yang bertanggungjawab, tingkah laku bertranspostrasi yang baik dan hanya membeli produk-produk yang ramah alam sekitar akan menyokong terciptanya kebiasaan sosial (habitus) yang baik. Hasil penyelidikan di Teheran menyebutkan pengubah arah yang berpengaruh terhadap tingkah laku pro alam sekitar antara lain adalah sikap terhadap alam sekitar. Sedangkan motif alam sekitar mempengaruhi tingkah laku pro alam sekitar berdasarkan hasil penyelidikan di Selandia Baru. Unsur-unsur motif alam sekitar seperti sikap altruistik, biosferik dan egoistik juga ikut menentukan tingkah laku seseorang baik lelaki mahupun wanita terhadap alam sekitar. Kebiasaan sosial (habitus) wanita ini akan memunculkan gerakan sosial masyarakat dan polisi kerajaan terhadap alam sekitar. Apa yang dilakukan NGO dan gerakan sosial lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk pengetahuan, motif dan sikap pro alam sekitar pula sehingga dapat menggambarkan apakah masyarakat bertingkah laku pro alam sekitar yang baik atau malah sebaliknya. Touraine (1977) mengatakan bahawa gerakan sosial memungkinkan masyarakat membangun orientasi mereka dan mengubahnya. Oleh kerana itu, menurut Eder (1985), perjuangan politik dalam gerakan sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah struktur sosial melalui pemunculan wacana alternatif (Brulle, 1996). Oleh kerananya dapat dikatakan bahawa gerakan sosial adalah aktiviti kreatif dari penduduk dalam membentuk diri mereka. 3.METODE PENELITIAN Pendekatan penyelidikan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penyelidikan ini melakukan studi terhadap fenomena yang ada dalam kelompok wanita bandar Jambi,Sumatera,Indonesia. Disamping itu kerana penyelidikan ini juga ingin mendapatkan rangkaian fenomena sosial dan budaya, alamiah dari kehidupan wanita bandar Jambi (Poerwandari, 2005). 3. 1. Subjek penyelidikan Informan atau responden atau subjek dalam penyelidikan ini, adalah populasi wanita bandar Jambi yang tinggal dan berinteraksi di sekitar lokasi yang menjadi tempat isu-isu alam sekitar di bandar Jambi. Dipilihnya bandar Jambi kerana bandar tersebut memiliki cakupan yang cukup tinggi dari sisi perkara alam sekitar. Mereka juga terpilih kerana mereka aktif berinteraksi dengan isu-isu persekitaran di bandar Jambi sehingga mereka dapat menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Jambi. Selain itu dilakukan juga temu bual terhadap beberapa orang aktivis wanita Kota Jambi untuk memperoleh gambaran mengenai aktiviti tingkah laku wanita Kota Jambi dan juga menemubuali Walikota Jambi sebagai informan kunci tentang kebijakan yang diambilnya dalam isi-isu persekitaran di bandar Jambi. 3. 2. Metode 181 Tipe pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah tipe pendekatan kajian kes feminis, karena ingin mengamati fenomena dan tingkah laku wanita di bandar Jambi berhubungkait dengan persekitarannya. Pendekatan ini digunakan kerana dapat memberikan pemahaman yang utuh dan terintegrasi mengenai keterkaitan wanita bandar Jambi dengan persekitaran. (Reinharz 2005), mengemukakan bahwa disamping menghasilkan dan menguji teori, tipe pendekatan kes kajian feminis juga bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam fenomena sepanjang masa, menganalisis kesignifikanan suatu fenomena sosial dan peristiwa-peristiwa di masa hadapan dan menganalisis hubungan antara bagian dari suatu fenomena. 3. 4. Teknik pengumpulan data Data yang diambil untuk menjawab pertanyaan penyelidikan ini diperoleh dengan teknik wawancara berstrata dengan menggunakan soalan. Wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan model analisisnya. Soalan wawancara dibuat sedemikian rupa sehingga pertanyaan yang diajukan dapat dimengerti oleh semua kalangan informan dan diupayakan seringkas dan sepadat mungkin kerana menyesuaikan dengan masa yang dimiliki informan untuk menjawabnya. Sebelum melakukan pengumpulan data, penyelidik mencoba membangun ”rapor” dengan subyek penyelidikan ini. Selain berempati pada pengalaman mereka dengan cara memposisikan diri pada situasi mereka dan memahami kebiasaan atau cara hidup mereka. Data kualitatif dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang utuh dengan tambahan maklumat yang dilakukan terhadap Walikota bandar Jambi, pejabat Jabatan Alam Sekitar bandar Jambi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, aktivis-aktivis wanita serta wanita-wanita dari pelbagai profesi, tingkatan usia, suku serta remaja dan kanak-kanak yang berdomisili di bandar Jambi untuk menyokong data kualitatif dengan menggunakan kajian kes melalui pemerhatian terlibat, temu bual, perpustakaan dan arkip: 182 3. 4. 1. Pemerhatian (Observasi) Bogdan secara lebih tepat mendefinisikan pengamatan berperan serta sebagai pengamatan yang bercirikan interaksi sosial yang memakan masa cukup lama antara penyelidik dan responden dalam lingkungan responden, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Selain itu penyelidik juga menggunakan observasi naturalistik iaitu pendekatan dimana penyelidik tidak menetapkan sebelumnya katagori dan klarifikasi, tetapi mengobservasi dengan cara dan latar yang alamiah (Gay dan Airasian, 2003). Adapun aspek yang diungkap dari observasi dalam penyelidikan ini adalah aspek dari tingkah laku wanita terhadap lingkungan. 3. 4. 2. Wawancara Wawancara yang dilakukan dalam penyelidikan ini adalah wawancara semi terstruktur, iaitu wawancara yang pertanyaannya ditentukan terlebih dahulu dan berbentuk open-ended question. (Gay dan Airasian, 2003). Dalam penyelidikan ini, penyelidik dilengkapi dengan pedoman wawancara yang berfungsi semata-mata untuk memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan, iaitu open-ended question(pertanyaanpertanyaan terbuka) yang bertujuan menjaga agar arah wawancara tetap sesuai dengan matlamat penyelidikan (Poerwandari, 2001). 3. 4. 3. Kepustakaan Kaedah ini membantu penyelidik untuk mendapatkan data mengenai latar belakang kelompok yang dikaji (Kota Jambi). Disamping itu, kaedah ini juga penting untuk mendapatkan data sekunder mengenai subyek penyelidikan iaitu tingkah laku wanita dan lingkungan. Data sekunder yang dihasilkan dari penyelidikan terdahulu akan dibandingkan dengan hasil penyelidikan dari kerja lapangan ini. Perbandingan antara dua data ini penting untuk mendapatkan gambaran sebenar mengenai tingkahlaku wanita terhadap lingkungan yang dikaji.Kajian ini akan dijalankan di Perpustakaan Utama Universiti Malaya dan Perpustakaan Kota Jambi 3. 4. 4. Dokumentasi Sebagian pustaka yang dipakai dalam penyelidikan ini adalah laporan status lingkungan daerah Kota Jambi, Perperpustakaan Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Kepala Bappeda Kota Jambi, Kepala Bapedalda Kota Jambi, Dinas Kebersihan Kota Jambi, NGO wanita, Lembaga Adat Daerah Jambi, Taman Budaya Jambi, Balai Pelayanan Informasi Kehutanan (BPIK) Badan Kehutanan Kota Jambi, Camat Kecamatan Pasar Jambi. 183 3. 5. Model analisis Merujuk dari uraian sebelumnya, khususnya dalam kerangka berpikir, maka dalam penyelidikan ini penyelidik mengajukan model analisis sebagai berikut - UMUR TINGKAT PENDAPATAN PENDIDIKAN PEKERJAAN LAMA DOMISILI SUKU BANGSA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA - ORIENTASI TINGKAH LAKU SUMBER INFORMASI ALAM SEKITAR PENGETAHUAN ALAM SEKITAR TINGKAH LAKU PRO ALAM SEKITAR (PRO ENVIRONMENTAL BEHAVIOR) MOTIF PRO ALAM SEKITAR SIKAP PRO ALAM SEKITAR Rajah 2. Model Analisis Dalam penyelidikan ini, penentuan informan lebih mempertimbangkan beberapa lokasi. Dimana di masing-masing lokasi diambil informan secara rawak. Apapun yang menjadi generalisasi dari hasil kesimpulan ini merupakan generalisasi untuk wilayah Kota Jambi saja. 3. 6. Teknik analisis data Teknik analisis data dimulai dengan langkah koding yaitu penyusunan transkrip verbatin dari hasil pengumpulan data, kemudian dilakukan penomoran pada tiap baris transkrip secara urut dan pemberian kode tertentu pada masing-masing berkas agar mudah diingat dan mewakili masing-masing berkas (Poerwandari, 2005 184 Analisis data selanjutnya adalah analisis tematik yaitu proses menemukan serangkaian tema yang mengambarkan fenomena tertentu. (Poerwandari, 2005). Teknik analisis tematik penting dalam penyelidikan ini karena selain sebagai cara menganalisis informasi kualitatif juga merupakan cara untuk mengamati aktivitas wanita Kota Jambi, interaksi kumpulan dalam sistem sosial masyarakat Kota Jambi, situasi di kawasan dan kebudayaan mereka. Berdasarkan tema-tema yang ditemukan, ditarik kesimpulan atau dugaan sementara. Dalam analisis tematik tidak terdapat kendala karena model analisis yang telah dibuat dalam bentuk skema sangat membantu. Penyelidik tinggal mengelompokkan tema yang muncul dari hasil wawancara ke dalam tiga tema besar dalam model analisis melalui sub-sub temanya. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi menurut subyek penyelidikan yang dalam hal ini wanita Kota Jambi. 4.TEMUAN DAN PEMBAHASAN Temuan dalam kajian ini, dimana permasalahan lingkungan dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh tingkah laku manusia termasuk tingkah laku wanita yang maladaptif. Oleh karennya perlu dicarikan solusi sesuatu yang boleh merubah tingkah laku buruk wanita terhadap lingkungan yang bersumber dari ”human behavior”. Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui perbaikan tingkah laku prolingkungan (proenvironmental behavior). Namun sebelum mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk memodifikasi tingkah laku wanita terhadap lingkungan perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang ada dibalik tingkah laku tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penyelidikan yang dilakukan di Kota Jambi ini mencoba memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi tingkah laku wanita tersebut sekaligus juga mengetahui apakah tingkah laku wanita terhadap lingkungan tersebut dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya lingkungan di dalam kehidupan. Hasil penyelidikan yang dilakukan di Kota Jambi ini adalah: 4. 1. Hasil penyelidikan ini terbukti bahwa perbedaan struktur wanita dalam masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran lingkungan seiring berjalannya waktu. Terbukti bahwa dipenyelidikan ini, tingkat pengajian, pendapatan dan suku bangsa tidak berpengaruh terhadap tingkah laku lingkungan. Dengan demikian teori tentang lapisan sosial tidak berlaku untuk menjelaskan tingkah laku prolingkungan di Kota Jambi sebagaimana dikatakan oleh Jonas dan Dunlap tentang The Broadening Bad Hypothesis. Kesimpulan ini hanya berlaku untuk Kota Jambi saja. 4.2. Teori dasar nilai concern lingkungan dari Stern dan Dietz (1994) yang mengembangkan teori Schwartz (1997) tentang model norma aktivasi, bahwa norma moral lingkungan dapat diaktivasi melalui nilai-nilai sosioaltruistik, biosferik dan egoistik masih dapat diterapkan untuk mengaktivasi concern lingkungan wanita Kota Jambi. Aktivasi tersebut dapat dilakukan pada wanita muda, wanita single yang sedang menempuh pendidikan, meningkatkan perhatian pada kaum wanita dan lebih gencar menyampaikan pesan-pesan lingkungan melalui media cetak dan elektronik serta papan maklumat RT. 4. 3. Menurut Mc. Farlanc dan Boxall, pengetahuan (knowledge) memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungan tingkah laku dan sikap lingkungan. Hasil penyelidikan ini memperkuat pendapat Farlanc dan Boxall bahawa pengetahuan berhubungan dengan tingkah laku pro lingkungan. Sedangkan yang mengaktivasi pengetahuan lingkungan adalah tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan peran media cetak dan elektronik serta papan informasi RT. 4.4. Peran pemerintah sangat dominan dalam membentuk habitus seperti yang dikatakan Bourdieu. Ini terlihat dari program Adipura yang selama bertahun-tahun ikut membentuk tingkah laku penduduk khususnya tingkah laku wanita terhadap lingkungan. 185 Walaupun setengah dipaksakan oleh instruksi dari tingkat atas, penduduk menta’atinya melalui peran Ketua RT, Lurah dan Kepala Kampung yang dibantu oleh pekerja sosioal (social worker). Sebagai perbandingan peran pemerintah juga menentukan keberhasilan program lingkungan yang dilakukan di Curitiba-Brazil yang selalu dijadikan model percontohan pengelolaan kebersihan kota oleh banyak kota-kota besar di dunia, Minamata (Jepun) dan Taipei (ROC Taiwan). Dalam keberhasilan program kebersihan lingkungan, di ketiga kota ini, tampak jelas peranan pemerintah yang dominan dibantu oleh partisipasi penduduk yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Untuk mengaktifkan gerakan sosial penduduk agar tingkah laku wanita baik terhadap lingkungan diperlukan seorang tokoh panutan yang dapat menggerakan wanitawanita untuk bertingkahlaku prolingkungan. Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan lapangan, habitus dan persekitaran (field) bukan hanya dibentuk oleh peranan pemerintah semata, tetapi juga diperlukan adanya kepemimpinan guna menggerakan sebuah gerakan sosial untuk membentuk suatu habitus baru. 4. 5. Sikap lingkungan terbentuk sebagai sebuah indikator dan komponen tingkah laku prolingkungan. Sikap proteksi lingkungan adalah sebuah konsep tiga dimensi yang meliputi environmental worldview,environmental concern dan environmental commitment (Cluck, 1997). Sikap proteksi lingkungan dalam penyelidikan ini mempengaruhi kelakuan pro lingkungan. Dengan demikian, penyelidikan ini membuktikan pendapat Cluck bahwa beberapa faktor boleh mengaktivasi sikap proteksi lingkungan yaitu motif lingkungan (nilai-nilai egoistik, biosfir dan altruistik), pernah mengikuti penyuluhan lingkungan dan peran aparat pemerintah mulai dari RT, Lurah dan Kepala Kampung sebagai pemberi pesan dan model lingkungan. 5.KESIMPULAN Adapun kesimpulan yang tidak mengeneralisasi untuk seluruh kawasan kota di Indonesia, karena penyelidik tidak melakukan perbandingan (komparasi) dengan kota lain yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang penyelidik dapatkan sekaligus menjawab pertanyaan penyelidikan tentang tingkah laku wanita telah di dorong dan menjadi gerakan sosial wanita prolingkungan di Kota Jambi adalah sebagai berikut: 5. 1. Hal-hal yang mendorong dan menjadi gerakan sosial wanita prolingkungan di Kota Jambi adalah tingkah laku prolingkungan yang terdiri dari pengetahuan, motif dan sikap. 5. 2. Adapunbentuk tingkah laku wanita terhadap lingkungan di Kota Jambi ada yang berupa motivator dan lain sebagainya. 5. 3. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh wanita untuk prolingkungan yang mampan (sustainable) di Kota Jambi antara lain menanam pohon, menghemat elektrik, memakai elektrik seperlunya saja dan lain-lain. 6.DAFTAR PUSTAKA Buku: Anonim, (tt), Aku bisa menghemat energi, Jakarta: PT. PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Anonim, (1997), Mengurangi emisi gas rumah kaca, Jakarta|: Algas Anonim, (1999), Metodhologi penyelidikan berperspektif perempuan dalam riiset sosial, Jakarta: Program studi kajian wanita program pascasarjana Universitas Indonesia Adriana Hernandez,.(1997), Pedagogy, democracy and fenism: rethinking the public sphere,USA: State University of New York. Al Adnani, A. F., (2008), Global Warming,Sebuah isyarat dekatnya akhir zaman dan kehancuran dunia, Granada: Mediatama 186 Anastasi, Anne, (1988), Psychological testing-Sixth edition, New Jersey: Prentice Hall, Inc Arief Budiman, (1985), Pembagian kerja secara seksual, sebuah pembahasan sosiologis tentang peran wanita di dalam masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia Arief Kristianto, (2010), Tanggap bencana alam banjir-Seri tanggap bencana, Bandung: Angkasa Aquarini Priyatna Prabasmoro, (2006), Kajian budaya feminis: Tubuh, sastra, dan budaya pop, Yogyakarta & Bandung: Jalasustra Azwar, I., (2003), Sikap manusia-Teori dan pengukurannya-Edisi ke-2 cetakan ke IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset A. Supratiknya, (2008), Statistik psikologi, Jakarta: PT. Grasindo B. Tresna Sasrtawijaya, (2009), Pencemaran lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta Bahar, Yul, H., (1986), Teknologi penanganan dan pemanfaatan sampah, Jakarta: Waca Utama Pramesti Bambang Wintoko, (TT), Panduan praktis mendirikan Bank Sampah, Yogyakarta: Pustaka Baru Press Bandarage, A., (1997), Women, population and global crisis, London: Zed Books Barber, S., Carroll, V., Mawle, A. and Nugent, C., (1997), Gender 21, women and sustainable development, London: UNED UK Barry, J., (2007), Environmet and social theory, 2th ed, Bell, P. A. et al.,.(1978), Environmental psychology, Philadelphia: W. B. Saunders Co Biehl, J., (1991), Rethinking eco-feminst politics, Boston-MA: South end Books Black, R., (1998), Refugees, environment and development, Harlow: Longman Bourdieu, P., (1984), A Social critique of the judgement of taste, CambridgeMassachusetts: Harvard University Press Breton, M. J., (1998), Women pioneers for the environment, Boston-MA: Northeastern University Press Buckingham-Hatfield, S., (2000), Gender and environment, London & New York: Routledge Budiharjo, E, dan Harjohubojo, S. (1993), Kota berwawasan lingkungan: Bandung: Alumni Burhan Bungin, (2010), Analisis data penelitian kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers Cadbury, D., (1997), The feminisation of nature: Our future at risk, Harmondsworth: Hamish Hamilton Cecep Dani Sucipto, (2012), Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Yogyakarta: Gosyen Publishing Chandler Barbour, at.all. (2005). Famlies, schools, and communities. USA: Pearson Merrill Prentice Hall Christine Skelton. (1989), Whatever happens to little women: gender and primary schooling, USA: Open University Press Coolican, Hugh, (1993), Research methods and statistics in psychology, Great Britain: Apek Typesetters Djam’an Satori, Aan Komariah, (2011), Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta Deddy Kurniawan Halim, (2008), Psikologi lingkungan perkotaan, Jakarta: Bumiaksara Dobson, A., (1999), Fairness and futurity: Essays on environmental sustainability, Oxford: Oxford University Press Edwards, Allen, L., (1957), Techniques of attitude scale construction, New York: Appleton-Century-Crofts Inc Emzir, (2012), Metodologi penelitian kualitatif-analisis data, Jakarta: Rajawali Pers 187 Epstein,J.L., Sanders,M.G.,Simon,B.,Salina,K.,Jansorn,N., & Van Voorhis, F. (2002), Schoos, familiy and community partnerships: Your handbook for action (2nd Ed.,). Thousand Oaks, CA: Corwin Press Faridah binti Nazir, Maridah binti Hj. Alias, (2013), Fonetik & Fonologi Bahasa Melayu, Malaysia: Penerbitan Multimedia, SDN. BHD F. Gunarwan Suratmo, (2009), Analisis mengenai dampak lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Giddens, A., (1985), Kapitalisme dan teori sosial modern-Suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber Gusti Ayu Ketut Surtiari, dkk, (2012), Adaptasi masyarakat perkotaan terhadap perubahan kualitas udara, Jakarta: Bidang Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) Hajah Noresah bt Baharom, BSc (UM)< MA (Birmingham)-Ketua Editor, (2010), Kamus Dewan-Edisi Keempat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Halley, NAD, (1999), The Best-Ever book of disasters, --: Kingfisher Publication Plc Hawkins, Osyoe, M., (tt), Kamus Dwi Bahasa Oxford Fajar, Bahasa Inggris-Bahasa Melayu, Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Edisi keempat, Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar, Sdn. Bhd Hendry Giroux, (1992), Border crossing: Cultural workers and the politics of education, New York dan London Herbert Grossman dan Suzanne H.Grossman, (1994), Gender issues in education, USA: Joekes, S., Green, C, and Leach, M., (1996), Integrating gender into environmental research, Brighton: IDS Publications Juli Soemirat Slamet, (2009), Kesehatan lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Kerlinger, F. N and H. B. Lee, (2000), , Orlando: Harcourt, Inc Foundations of behavioral research, 4 th-ed Kerlinger, Fred N and Elazar J. Pendhazur, (2001), Multiple regression behavioral research, USA: Holt, Rinehart & Winston, Inc Kusnoputranto, Haryoto, (1983), Kesehatan lingkungan, Jakarta: FKM-UI Kristi Poerwandari, (2001), Pendekatan kualitatif untuk penelitian tingkah laku manusia, Jakarta: Lembaga pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikologi (LPSP3)-Fakulti Psikologi-Universitas Indonesia Mann, Richard, (1994), Perjuangan untuk lingkungan, Canada|: Gateways Books Manschot, Chaterine A., (1991), Urban solid waste management system for the city of Jakrta-Indonesia: An assessment of conventional solid waste management, an alternative solid waste management system, and a feasibility stuudy of integrated resource recover, USA: York University Mar’at, (1981), Sikap manusia-perubahan serta pengukuran, Jakarta: Ghalia Indonesia McNaughton, S. J., & L. L. Wolf, (1990), General ecology: Second Edition: New YorkUSA: Holt, Rinehart and Winston Mohamad Soerjani, Arief Yuwono dan Dedi Fardiaz, (2007), The living environmentEducation, environmental management and sustainable development, Jakarta:Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan Moleong, Lexy J,. (2000), Metodologi penyelidikan kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nanang Martono, (2011), Sosiologi perubahan sosial-Perspektif klasik, modern, posmodern dan poskolonial, Jakarta: Rajawali Press 188 Nicolas, C., Tijah Yok Chopil & Tiah Sabak, (2003),Orang asli women and the forest, Subang Jaya: COAC Outerbridge, Thomas B, (1991), Sisa pepejal padat di Indonesia; perkara atau sumber daya?. Ed. Ke 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Otto Soemarwoto, (1991), Indonesia dalam kancah isu lingkungan global, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Oskamp, S., (2000), A sustainable future for humanity? How can psychology help? American psychologist Oxlade, Chris, (2007), Mengenal bencana alam: Banjir, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Parker, Russ, (2009), Selamatkan bumi kita: Krisis pengelolaan sampah, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Parsudi suparlan, (1994), Metodologi penelitian kwalitatif, Jakarta: Program kajian kawasan Amerika program pascasarjana Universitas Indonesia Plumwood, V., (1993), Feminism and the mastery of nature. London: Routledge Putnam Tong, Rosemarie, (1998), Feminist thought: A more comprehensive introductionsecond edition, Colorado: Westview Press Ratna Dwi Santoso, Mustadjab Hary Kusnadi, (1992), Analisis Regresi, Yogyakarta: Andi Offset Ritzer, G., (1996), Modern sociological theory-fourth edition, USA: Mc Graw-Hill Companies ________ , (2007), Teori sosiologi modern-edisi ke-6, cetakan ke-4, Riyadi, AL. Slamet, (1984), Kesehatan lingkungan, Surabaya: Karya Anda Rose, G.,(1993), Feminism and geography: The limits of geographical knowledge. Cambridge: Polity Press Rosli Umar, (2002), Sungai Selangor Dam: Orang asli and the environment. In people before profits. The rights of Malaysian Communities in development. Edited by Kua Kia Soong, Kuala Lumpur: SIRD and SUARAM Saifuddin Azwar, (1997), Reliabilitas dan validitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sarlito Wirawan Sarwono, (1992), Psikologi lingkungan, Jakarta: Program pascasarjanaprogram studi psikologi Universitas Indonesia dengan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Seager, J., (1993),Earth follies: feminism, politics and the environment, London: Earthscan Sevilla, Consuelo, G., at all, (1988), An introduction in research methods, Philippines: Rex Printing Company Simmons, I., (1997), Humanity and environment, Harlow: Addison, wesley, Longman Smith, Jonathan, A, (2008), Qualitative psychology: A practical guide in research methods, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore & Washington DC: Sage Publications Soeryani, M, (1997), Pembangunan dan lingkungan: Meniti gagasan dan pelaksanaan sustainable development, Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan Sondang K, Susanne Siregar, Anto Ikayadi (Ed), (2008), The hot children soup for global warming-Refleksi kritis anak Indonesia tentang krisis alam sekitar, Depok: Aksara pustaka Soemarwoto, Otto, (1983), Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan, Bandung: Djambatan Soeryani, Muhammad, Ahmad, Rafiq, Munir, Rozy, (1987), Lingkungan, sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan, Cetakan ke 1, Jakrta: UI Press Sudjana, (1992), Metoda statistika, Bandung: Tarsito Sugiyono, (2010), Memahami penelitian kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta 189 Sukamto Hadisuwito, (2012), Membuat pupuk organik cair, Jakarta: PT Agromedia Pustaka Sumadi Suryabrata, (2000), Pengembangan alat ukur psikologis, Yogyakarta; Andi Suminaring Prasojo, (2012), Memupuk uang dari sampah, cara kaya dengan kompos, Jakarta: Bestari Susan Buckingham-Hatfield, (2000), Gender and environment, London: Routledge Tashakkorim, Abbas, Teddlie, Charles, (2010), Mixed methodology-combining qualitative and quantitave approaches, California: Sage Publications Tham, P. (Ed), (2011), Longman kamus dwibahasa, Bahas Melayu-Bahasa Inggris, Bahasa Inggris-Bahasa Melayu, Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia, SDN, BHD Turner, Jonathan H, (1997), The strusture of sociological theory-Sixth Edition Ully Hary Rusadi, (1996), Buku panduan: Pandu lingkungan Indonesia, Jakarta: (tidak ada penerbitnya) Vanessa Griffen, (2001), Seeing the forest for the people-a handbook on gender, forestry and rural livelihoods, Kuala Lumpur: APDC GAD Programme Wisno Arya Wardhana, (2010), Impak pemanasan global, Yogyakarta: Andi offset Yayasan Garuda Nusantara, (1997), Peranan wanita dalam lingkungan lestari, Edisi Pertama, Jakarta; Inti Surya Yusmar Yusuf, (1991), Psikologi antar budaya, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Zoer’aini Djamal Irwan, (2009), Besarnya eksploitasi perempuan dan lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Serial: Cluck, R., et al., (1997), Attitudes towards and commitment to environmentalism: A multidimentional conceptualization, Canada:Toronto-Ontario: Paper presented at the 60 th meeting of the rural sociological society Dietz, Frey & Rosa (2000), Risk assesment and management. The environment and sociaety reader.USA: A pearson education company Hague, Paul, Harris, Paul, (1995), Sampling & statistika, Seri praktis No. 9, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo Kalantari, K. Fami, H. S., Asadi, A, & Mohammadi, M, (2007), Investigating factors affecting environmental behavior of urbanresidents: A case study in Tehran CityIran, American Journal of environmental sciences 3 (2) Kennedy, John, E., (2009), Era bisnis ramah lingkungan-seri marketing communication, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Lee, A. E & Norris, J. A., (2000), Attitudes toward environmental issues in East Europe, International Journal of Public Opinion Research Vol 12 No. 2 McFarlanc, B. & Boxall, P, (2003), The role of social psychological and social structural variables in environmental activism: An example of the forest sector, Journal Environmental Psychologist Merton, R. K., (1938), Social structure and anomie. American sociological review 3 Miller, J. D., (1990), The public understanding of science and technology in the United States, 1990 (A report submitted to the national science foundation), IL: Public Opinion Laboratory Pembangunan sosial dan persekitaran, (2006), Jurnal sosiologi masyarakat, Edisis|: Vol XIII, No. 2 Disember 2006 Schultz, P.W., (2001), The structure of enviromental concern: concern for self, other people and biosphere, Journal of environmental psychology-21 190 Stern, P. C., & Dietz, T., (1994), The value basis of environmental concern, Journal of social issues 50, 65, 84 Stern, P. C., & Dietz, T., Kalof, L., & Guagano, G. A., (1995), Values, beliefs, and proenvironmental action: Attitude formation toward emergent attitude objects, Journal of applied social psychology-25 Tarrow, S., (1989), Struggles, politics and reform: Collective action social movemets, and cylcle of protest. Western societies program occasional paper no. 21, Center for international studies, cornell university Peraturan dan Sumber Lain: Anonim, (2001), Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Jakarta: Bapedal Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2005), Pembangunan manusia berbasis gender, Jakarta: Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Bapedalda Kota Jambi. (2007), Status lingkungan kawasan Kota Jambi tahun 2008, Jambi: Bapedalda Camat Pasar Jambi dengan Koordinator Statistik Kecamatan Pasar Jambi, (2010), Kecamatan Pasar Jambi dalam Angka-Pasar Jambi in Figure, Jambi: Kecamatan Pasar Jambi Pemerintah Kota Jambi, (2007), Buku putih sanitasi Kota Jambi tahun 2007, Jambi: Pemkot Bandar Jambi. _____________________, (2007), Buku data status lingkungan kawasan Kota Jambi, Jambi: Pemkot Bandar Jambi Pemerintah Kota Jambi bekerjasama dengan Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, (2004), Ikhtisar adat Melayu bandar Jambi-Cetakan ke II, Jambi: Pemkot Bandar Jambi _____________________, (1993), Buku pedoman adat Jambi, Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi _____________________, (2003), Dinamika adat Jambi dalam era global, Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi ______________________, (2006), Himpunan materi pembekalan adat istiadat melayu Jambi bagi para Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan para pengurus Lembaga Adat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Angkatan ke VI dan VII, Jambi: Lembaga Adat Melayu Jambi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Persekitaran Permukiman Nomor 281-II/P. D. 03. 04. L. P tahun 1989 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan sampah, Jakarta: Kantor Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Latihan Ilmiah: Anonim, (2000), Cara mudah dan cepat memanfaatkan sampah menjadi kompos, Jakarta: Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2000 Soeriaatmadja, RE, (1984), Program penanggulangan sampah domestik, Jakarta: Makalah disampaikan pada Kamus Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Zawawi Ibrahim, Sharifah Zarina Syed Zakaria, (2009), Environment and social science perspectives in Malaysia, Malaysia: Akademika 76 (Mei-Ogos 2009, 41-64) Surat Sebaran dan Risalah: 191 Kementrian Kesihatan Malysia, (----), Awas ! Penyakit bawaan air dan makanan, Anda boleh mengelakannya, Malaysia: Bahagian Pendidikan Kesihatan dengan kerjasama Bahagian Kawalan Penyakit Kementrian Kesihatan Malaysia Akhbar dan Majalah: Jambi Ekspres, (2011), Sampah di RT 19 Pasir Putih butuh perhatian, Jambi: Rabu 23hb Maret 2011, muka surat 16 lajur 2, 3, 4, 5, 6 ------------------, (2011), Pengelolaan sampah terkendala angkutan, Jambi: Sabtu 16hb April 2011, muka surat 24 lajur 2, 3, 4 ------------------, (2011), Pasang iklan di pohon bisa merusak, Jambi: Sabtu 16hb April 2011, muka surat 24 lajur 1, 2, 3, 4 ------------------, (2012), Titik api bertambah, Jambi: Selasa 18hb September 2012, muka surat 21 lajur 2, 3, 4 ------------------, (2012), Kabut asap makin merajela, sebahagian siswa SD dan TK diliburkan, Jambi: Selasa 18hb September 2012, muka surat 1 lajur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ------------------, (2012), Penerbangan kembali terganggu, Jambi: Khamis 06hb September 2012, muka surat 1 lajur 3, 4 ------------------, (2012), Jasa pengiriman barang rugi, Jambi: Isnin 01hb Oktober 2012, muka surat 0 lajur 2 ------------------, (2012), Kabut tak sehat lagi, Jambi: Isnin 01hb Oktober 2012, muka surat 9 lajur 3, 4 Media Indonesia, (1993), Media Indonesia, Jakarta: 25hb Juni 1003, muka surat 4 lajur 1 Posmetro Jambi, (2011), Iklan polusi udara, Jambi: Senin 14hb November 2011, muka surat 12 lajur 1 R.Valentina, (2003). Kompas, Jakarta: Tribun Jambi, (2011), Himbauan kerajaan bandar Jambi, Jambi: Senin 14hb November 2011, muka surat 12 lajur 1 ------------------, (2012), Cuaca ekstrem mengintai, Hujan deras disertai angin kencang, Jambi: Isnin 22hb Oktober 2012, muka surat 9 lajur 5, 6, 7 --------------------, (2012), Masih berstatus siaga IV, Kondisi debit air di bandar Jambi, Jambi: Rabu 12hb Disember 2012, muka surat 9 lajur 2, 3, 4 --------------------, (2012), Menangis, Jambi: Rabu 26hb Disember 2012, muka surat 16 lajur 2 --------------------, (2012), Drainase burok, Jambi: Sabtu 03hb November 2012, muka surat 8 lajur 1 -------------------, (2012), Berenang, Jambi: Rabu 26hb Disember 2012, muka surat 16 lajur 1 -------------------, (2012), Sampai kapan melawan asap, Jambi: Juma’at 28hb September 2012, muka surat 10 lajur 1 --------------------, (2012), Kalah dengan asap, Jambi: Selasa 02hb Oktober 2012, muka surat 10 lajur 1 -------------------, (2012), Bandara Jambi lumpuh, Semua penerbangan dibatalkan, Jambi: Khamis 27hb September 2012, muka surat 1 lajur 5, 6 -------------------, (2012), Lion Air Mendarat di Palembang, Sore jarak pandang 1000 meter, Jambi: Ahad 30hb September 2012, muka surat 3 lajur 1, 2, 3, 4 --------------------, (2012), Kabut asap makin pekat, Pengendara motor diimbau pakai masker, Jambi: Isnin 07hb Oktober 2012, muka surat 17 lajur 5, 6, 192 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA Dr. Shirley Y. V. I. Goni., S.Sos. M.Si Staf Pengajar di FISPOL Unsrat, 193 email : [email protected] Abstrak Secara formal, sebenarnya tidak ada satu aturan pun yang mendiskriminasikan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan publik lainnya. Namun faktor manusia, nilai-nilai sosial budaya, struktural dan kelembagaan, penerapan tata pemerintahan yang belum spenuhnya tidak tanggap gender, belum optimalnya political will dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan gender mainstreamin menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara yang banyak memberikan ruang dan peran kepada perempuan dalam memimpin daerah maupun satuan kerja pemerintahan daerah.Dengan menetapkan kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dikaji dari perpektif gender sebagai objek kajian dan mengambil lokasi di Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa bahwa kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dikaji dari perpektif gender banyak menggambarkan penerapan teori kontingensi situasional juga menerapkan gaya perilaku kepemimpinan birokrasi yang mengutamakan pada prosedur, peraturan dan mekanisme kerja dengan tidak melupahkan pengembangan hubungan informal dalam rangkah mengimbangi hubungan formal yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan setiap hari. Oleh karenanya guna mewujudkan keberhasilan kepemimpinan maka diperlukannya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam pengembangan kemampuan individu dan kelompok yang dipimpinnya. Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Pemerintahan Daerah. 1.PENDAHULUAN Interaksi di dalam kehidupan manusia membentuk pola hubungan saling sejajar atau vertikal maupun saling mendominasi. Dalam kaitannya dengan penggunaan kata pemerintahan yang berasal dari kata pemerintah dan terbentuk dari kata perintah yang memiliki arti menyuruh menyelesaikan suatu pekerjaan. Peristiwa yang terjadi dalam proses pemerintahan ini merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia dan merupakan gejala sosial. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wasistiono (2002:5) bahwa pemahaman akan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan. Sehingga dapat dikatakan “peristiwa atau gejala pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok” (Ndraha, 1997:6). Peristiwa atau gejala pemerintahan yang dipahami sebagai gejala sosial dalam hubungan anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok juga tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan salam sistem birokrasi yang memerlukan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan suatu organisasi perangkat daerah. Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki lima belas kabupaten/Kota sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota perna dipimpin oleh enam orang bupati/walikota perempuan dan dua orang wakil bupati/wakil walikota perempuan, tiga orang perempuan sekretaris daerah dan lebih dari dua puluh kepala satuan kerja perangkat daerah perempuan. Dalam penyelenggaraan 194 pemerintahan sampai dengan saat ini tidak satupun yang terkait dengan masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya baik bupati/walikota, sekretartis daerah maupun kepala satuan kerja perangkat daerah. Situasi yang demikian ini menjadi suatu yang menarik dalam kajian social humaniora mengingat dewasa ini tidak sedikit pejabat birokrasi yang gagal menjalankan pemerintahan daerah dan bahkan banyak diantaranya yang harum mengahiri periode pemerintahan di balik jeruji besi. Fenomena permasalahan ini harus diakui tidak dapat dipisahkan dari proses kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan termasuk didalamnya para perempuan yang diberi kepercayaan untuk memimpin daerah atau satuan kerja perangkat daerah. Dengan memahami fenomena permasalahan diatas, kajian ini difokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dikaji dari perspektif gender. 2.METODE PENELITIAN Penelitian ini menetapkan kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dikaji dari perspektif gender sebagai objek kajian dengan mengambil lokasi di Provinsi Sulawesi Utara. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif (Creswell, 1994). Dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan akan data dan informasi, maka data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu perempuan yang pernah menjadi dan sementara menjabat sebagai Bupati/Walikota/Wakil Bupat/Wakil Walikota, mantan Sekretaris Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, serta didukung dengan observasi dan penggunaan dokumen yang terkait kepemimpinan perempuan. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tahapan kategorisasi dan mereduksi data, data dan informasi yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, melakukan interpretasi pada data, pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi dan melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan yang didasarkan pada kesimpulan (Triangulasi). 3.HASIL DAN PEMBAHASAN Pemahaman akan perempuan dalam proses kerja dan interaksi sosial dewasa ini lebih dikenal dengan istilah gender. Gender adalah sekumpulan nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki- laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki - laki dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa (Brett, 1991). Gender adalah suatu ciri yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Faqih, 1996). Pembedaan Gender berdampak terhadap pembedaan dalam distribusi kekuasaan antara laki- laki dan perempuan, hal ini selanjutnya berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam akses dan kontrol terhadap pendapatan. Sejarah pembedaan Gender antara laki- laki dan perempuan terbentuk melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, diperkuat dan dilembagakan baik secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan dan bahkan melalui peraturan-peraturan negara. Sehingga sering dianggap bahwa ketentuan Gender tersebut merupakan ketentuan yang tidak dapat dirubah karena dianggap sebagai ketentuan yang sudah sewajarnya. Pembedaan secara gender sebenarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Namun yang menjadi masalah ternyata pembedaan Gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki- laki dan (terutama) bagi kaum perempuan. Bentuk ketidakadilan dan penindasan tersebut antara lain berupa subordinasi, 195 diskriminasi, marjinalisasi, kekerasan, pelebelan negatif serta beban kerja yang berat sebelah (Faqih, 1996). Manifestasi dari ketidakadilan gender tersebut membawa akibat terhadap timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan. Persoalan Gender adalah persoalan hubungan laki- laki dan perempuan, suatu hubungan dimana dalam banyak kasus perempuan secara sistematis disubordinasikan. Gender menjadi persoalan ketika nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan gender tersebut menghambat seseorang untuk mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya dan hasil-hasilnya. Dominasi ekonomi laki- laki yang merupakan terjemahan dari ‘kekuasaan laki- laki', telah menggiring perempuan ke dalam kedudukannya sebagai orang kedua yang kurang begitu penting dibandingkan dengan laki- laki. Dalam sebagian besar masyarakat anggapan laki-laki sebagai pencari nafkah utama atau laki-laki sebagai pekerja produktif sangat dominan meskipun kenyataannya tidak demikian. Laki- laki senantiasa beranggapan bahwa dalam keluarga mereka memegang peran sebagai penghasil pendapatan utama dan penentu segala keputusan. Hal ini tetap berlangsung meskipun dalam keadaan dimana pengangguran laki- laki tinggi dan kerja produktif perempuan sesungguhnya memberikan penghasilan utama. Subordinasi terhadap perempuan sering menempatkan perempuan pada situasi yang tidak menguntungkan, seperti perempuan tidak mempunyai posisi untuk mengambil keputusan. Sementara itu berkaitan dengan kepemimpinan secara harfiah kepemimpinan dipahami bahwa kepemimpinan diadopsi dari bahasa inggris yaitu leadership. Leadership berasal dari akar kata to lead yaitu berupa kata kerja yang berarti memimpin, Lebih lanjut kepemimpinan tersebut dapat dipahami sebagai to show the way to by going in advance. Bertolak dari pengertian secara harfiah tersebut diatas maka dengan demikian memimpin merupakan suatu pekerjaan seseorang tentang bagaimana cara untuk mengarahkan (direct) orang lain (Sulistiyani, 2008:9). Adapun pemaknaan secara terperinci artinya kepemimpinan juga harus dipahami dari sisi pelaku kepemimpinan, yang disebut dengan istilah leader (pemimpin), yaitu orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk memimpin. Pemimpin merupakan orang yang menjalankan kepemimpinan atau dapat dimengerti sebagai a person who leader other a long way guidence.(Sulistiyani, 2008:10). Dari pengertian ini jelaslah bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin orang lain, dengan cara memberikan petunjuk, atau dengan dimaknai secara lebih formal bahwa dalam menjalankan kepemimpinan seseorang tersebut memberikan perintah-perintah. Dengan pengertian ini maka kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pemimpin sebagai subyek yang menjalankan peran untuk memimpin tersebut sangat penting. Muara dari pemahaman kepemimpinan ini terletak pada “proses”. Proses tersebut menunjukan interaksi antara pemimpin dengan anak buah dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan pada pemaknaan secara harafiah tersebut, maka dalam memahami kepemimpinan sebaiknya juga melihat bahwa konsep kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, sehingga orang tersebut dapat menjalankan fungsi kepemimpinan secara memadai. Banyak konsep kepemimpinan dari para ahli administrasi dan manajemen. Salah satunya adalah konsep kepemimpinan menurut Joseph C.Rost, (2004:3) yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Sementara itu Nawawi (2016:18) yang didasarkan pada pendapat Churchil mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan mnegarahkan, merupakan factor (aktivitas) penting dalam efektivitas manajer/pemimpin. Dalam perkembangannya, kepemimpinan dapat dilihat dari teori Great Man dan teori Big Bang, teori sifat/kepribadian, teori perilaku maupun teori kontingensi, serta tipe 196 otoriter, demokratis, bebas dan gaya kepemimpinan ahli/ekspert, kharismatik, paternalistic dan transformasional (Nawawi, 2016 : 72). Pesatnya perkembangan kepemimpinan dalam kajian ilmiah menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan sentral di dalam sebuah kelompok (organisasi) dengan seorang pemimpin puncak sebagai figure sentral yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengefektifkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dikaji dari perspektif gender banyak menggambarkan penerapan teori kontingensi situasional. Yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard adalah yang memberikan penekanan pada pengikut-pengikut dan tingkat kematangan mereka. Para pemimpin harus menilai secara benar atau secara intitutif mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya dan kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan tersebut. Penerapan kepemimpinan situasional ini menjadikan kepemimpinan yang efektif yang diwujudkan melalui kemampuan memilih perilaku atau gaya kepemimpinan yang tepat berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan anggota organisasi atau bawahan. Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai kesejahtraan rakyat melalui efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maka daerah diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam hubungannya antara pemerintah dengan warga negara makna pemerintah yang diberi istilah governance (tata pemerintahan) sebagai pendamping kata government telah mengubah secara mendalam praktek – praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup dimensi struktur, fungsional dan kurtural. Perubahan struktur berkaitan dengan struktur hubungan pemerintah ousan dan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif maupun struktur hubungan pemerintah dengan masyaraka. Perubahan fungsional berkaitan dengan perubahan fungsi – fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, dan perubahan kultur berkaitan dengan perubahan pada tata nilai dan budaya yang mendasari hubungan kerja intraorganiasi, antarorganisasi maupun ekstraorganisasi termasuk didalamnya pada peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan pemerintahannya, para perempuan yang memimpin satuan kerja perangkat daerah selalu mempertimbangkan kemampuan dari para bahawannya, sehingga dari data lapangan ditemukan bahwa upaya untuk menjadikan bawahan memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas yang dipercayakan dan menjadikan kepemimpinannya berjalan dengan baik banyak memperkuat bawahan dengan mengikutsertakan pada berbagai pendidikan dan pelatihan (memperkuat pengembangan sumberdaya aparatur). Akan tetapi sekalipun cenderung menggambarkan teori kontingensi situasional namun juga menerapkan gaya perilaku kepemimpinan birokrasi yang mengutamakan pada prosedur, peraturan dan mekanisme kerja menjadi salah satu hal yang selalu dijadikan pijakan dalam mengawasi proses kerja para bawahannya, dengan tidak melupakan pengembangan hubungan informal dalam rangka mengimbangi hubungan formal yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan setiap hari. Mencermati penerapan teori dan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh perempuan pada penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara dalam kaitannya dengan pendapat Huntington dan Nelson (1990: 16) menunjukkan bahwa Partisipasi merupakan suatu tindakan sukarela untuk mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi politik yang dilakukan setiap orang baik itu 197 partisipasi yang bersifat legal atau ilegal, tetap memiliki nilai pendidikan politik bagi setiap individu. Karena dengan setiap orang terlibat dalam berbagai kegiatan politik secara sadar atau tidak sadar, hal tersebut dapat memberikan penambahan nilai tentang arti dan makna dari politik. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari bagan berikut ini. Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penguasa (pemerintah) dan sisi warganegara. Dari sisi pemerintah hakikat partisipasi politik mengandung makna sebagai pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat (warga negara, rakyat) dalam bentuk memberi kesempatan untuk berperan serta memikirkan masalah kehidupan negara melalui kegiatan pemilihan (dipilih) individu-individu yang akan duduk dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Masyarakat dapat menentukan pilihannya (dipilih) sesuai kepercayaan yang mereka yakini terhadap pilihan tersebut. Keberhasilan perempuan dalam pentas pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara melalui kepemimpinan yang dijalankan mengubah pola pikir tentang budaya patriarki yang menempatkan perempuan subordinat laki-laki. Keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinannya semakin menunjukkan bahwa kendala struktural dan kultural yang dahulunya yang mengakibatkan marjinalisasi terjadi dalam budaya, birokrasi, maupun program pembangunan dapat terbantahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Sekalipun memang secara formal, sebenarnya tidak ada satu aturan pun yang mendiskriminasikan perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan maupun dalam kehidupan publik lainnya. Oleh karenannya melalui penelitian ini menjadi semakin nyata bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan kedudukan hukum perempuan dalam bidang politik pemerintahan di tingkat kebijakan yang sudah dilakukan sejak lama oleh pemerintah. Misalnya saja dengan mertifikasi Konvensi PBB tentang hak politik perempuan (1953), malalui UU No.68 Tahun 1956 serta konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No.7 Tahun 1984 dan UU Pemilu No.12 Tahun 2003 yang menjamin quota 30 persen keterwakilan perempuan telah juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah tantangan dalam lebih mengembangkan kepemimpinan perempuan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah selain perlu diperhatkan faktor nilai-nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai, citra-baku/stereotype, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang ”menempatkan” laki-laki di posisi pemimpin, penentu, dan pengambil keputusan dengan kedudukan superio dan pada akhirnya menyebabkan perempuan menjadi warga negara kelas dua, didiskriminasikan dan dimarjinalkan (isu gender), juga faktor manusia. Perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik dan kehidupan publik/pemerintahan , karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ''ditempatkan'' dalam lingkup kehidupan rumahtangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah daripada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik. Karena itu, kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Menyikapai hal tersebut, maka diperlukannya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam pengembangan kemampuan individu maupun dalam kelompok. Nawawi (2006 : 229) mengungkapkan bahwa selama jangka waktu yang panjang, teori – teori kepemimpinan pada umumnya mendukung pendapat bahwa keberhasilan dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional seoraang pemimpin. Kecerdasan intelektual dibutuhkan oleh pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organsiasi yang dipimpinnya serta dalam membantu anggota organisasi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok masing – masing. Demikian pula halnya dalam upaya mempengaruhi orang lain dan 198 membantu bawahan menyelesaikan permasalahan yang ada maka pemimpin memerlukan kecerdasan emosional. Berbagai perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin berupa kesediaannya menerima kritik, saran, pendapat dari pihak luar dalam memecahkan masalah sebagai bentuk kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional menjadi penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, sebab pola orientasi kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin termasuk para perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah setidaknya berorientasi pada pelaksanaan tugas pekerjaan secara tepat dan benar, memperhatikan anggota organisasi atau berorientasi pada manusia yang disesuaikan dengan situasi/kondisi anggota organisasi sebagai manusia yang unik dan kompleks, juga berorientasi kepada hubungan dan mementingkan hasil kerja sesuai denganstandar yang berlaku sebagai pedoman kerja sebagaimana kebijakan yang ada. 4.KESIMPULAN Berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditemukan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang dikaji dari perpektif gender banyak mengdeskripsikan penerapan teori kontingensi situasional dan menerapkan gaya perilaku kepemimpinan birokrasi yang mengutamakan pada prosedur, peraturan dan mekanisme kerja dengan tidak melupakan pengembangan hubungan informal dalam rangka mengimbangi hubungan formal yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan setiap hari. Kepemimpinan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi politik yang terwujud dalam bentuk perilaku kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keberhasilan perempuan dalam pentas pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara melalui kepemimpinan yang dijalankan mengubah pola pikir tentang budaya patriarki yang menempatkan perempuan subordinat laki-laki. Keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinannya semakin menunjukkan bahwa kendala struktural dan kultural yang dahulunya yang mengakibatkan marjinalisasi terjadi dalam budaya, birokrasi, maupun program pembangunan dapat terbantahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya, menjadi tantangan dalam lebih mengembangkan kepemimpinan perempuan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah selain perlu diperhatikan faktor nilai-nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai, citra-baku/stereotype, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki juga faktor manusia. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukannya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dalam pengembangan kemampuan individu maupun dalam kelompok dalam kepemimpinan. Sebab teori – teori kepemimpinan yang berkembang sampai saat ini mendukung bahwa keberhasilan dalam mengefektifkan organisasi untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional seorang pemimpin. 5.DAFTAR PUSTAKA Brett, A., 1991, Why Gender is A Development?, dalam Buku Changing Perceptions: Writing on Gender and Development, Tina Wallace (ed.), London. Creswell, John W. 1994. Qualitative Inquiry and Reasearch Disign. California: Sage. Faqih, M., 1996, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 199 Huntington., S.P dan Joan, Nelson. J. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta. Nawawi. Handari. 2016. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta. Rost. Joseph C. 2004. Kepemimpinan. Terjemahan Triantoro Safaria. Graha Ilmu: Jakarta Sulistiyani. Ambar Teguh dan Rosidah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta. Wasistiono. Sadu. 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqa Print, Bandung. MOBILISASI SUMBER DAYA DAN IDENTITAS KELOMPOK DALAM MENOLAK RANPERDA DISKRIMINATIF (STUDI KASUS: GERAKAN FKWIS SUMATERA BARAT, 2001) Selinaswati, MA, Phd Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Uiversitas Negeri Padang Email: [email protected], [email protected] Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi aksi bersama anggota Forum Komunikasi Wartawati Sumatra Barat-FKWIS menolak Draft Ranperda diskriminatif. Gerakan organisasi dipengaruhi era Reformasi tahun 1998, paralel dengan kebijakan sistem otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi pemimpin lokal seperti anggota DPRD membuat Perda yang bernuansa lokal. Salah satu produk yang dusulkan Komisi E DPRD periode 199- 200 2004 adalah Ranperda Penyakit Masyarakat (Pekat). Pasal 10 ayat 3 Ranperda tersebut tentang pelarangan perempuan untuk tidak beraktifitas di malam hari setelah jam 8 malam hingga jam 6 pagi bila tak ada muhrim yang mendampingi. Jadi gerakan FKWIS menolak klausul Ranperda tersebut agar tidak menjadi Perda, sebab dikhawatirkan menghambat perempuan yang melakukan aktifitas dan dinas di malam hari. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian kualitatif berupa observasi dan wawancara mendalam kepada pimpinan FKWIS, sejumlah wartawati, pihak komisi E DPRD dan pemuka masyarakat seperti Bundo Kanduang. Hasil penelitian menunjukkan gerakan yang dilakukan FKWIS, yang menggunakan identitas kolektif mereka sebagai jurnalis berhasil menuntut dihapusnya pasal diskriminatif, yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dalam kapasitas sebagai wartawati; memanfaatkan media untuk mengakses, mengimformasikan serta membentuk opini publik melalui talk show, dialog interaktif, polling sms dan seminar. Mereka juga membuka dialog, komunikasi dan membangun jaringan dengan organisasi dan pihak lain guna mendapat dukungan. Kata kunci : Gerakan sosial, gerakan perempuan, mobilisasi sumber daya, identitas kolektif Abstract This paper examined the collective action of female journalist organization in order to oppose the draft local regulation that would discriminate women. The organization known as ‘Women’s Journalist Forum in West Sumatra’ or ‘Forum Komunikasi Wartawati Sumatera Barati’. The movement was triggered by Reform Era in 1998 as well as the change of government systems from a centralized to decentralized system. The aim of movement to oppose Article X Number three which banned women to go out at night from 10 pm to 6 am without their mahram or husband. By using qualitative approach method, observation and in-depth interview have been done with the leader of FKWIS, some female journalists and traditional leader. The research found that FKWIS organization used resource mobilization and collective identity during their movement. Resources mobilization can be seen through media usage; utilizes media to make public opinions, access to network and building network while collective identity showed how do the members of this group organize and create their identity for their collective action. Both resource mobilization and collective identity were used to analyze the effort of their activities influence people’s mindset to refuse the draft act and to raise gender awareness. Keyword: Movement, Women’s Movement, Resource Mobilization, Collective Identity 1. Pendahuluan Gerakan sosial merupakan aksi kolektif atau gerakan kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuan tersebut untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan dan kepentingan para anggota kelompok atau organisasi bersangkutan. Gerakan sosial memiliki implikasi pada terbentuknya perubahan sosial (Sztompka, 2007). Berbagai macam bentuk gerakan atau pergerakan sosial bisa dilihat dari aksi yang dilakukan organisasi atau kelompok dengan identitas tersendiri dan ciri khas masing-masing. Seperti pergerakan nasional yang bertujuan memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut berbagai organisasi politik, pemuda dan organisasi yang beranggotakan perempuan melakukan aksi dan kegiatan. Bentuk lain dari gerakan sosial, gerakan pencinta lingkungan (Green Peace) bertujuan untuk keberlangsungan dan kebertahanan lingkungan hidup, aksi organisasi 201 buruh sebagai bentuk gerakan sosial buruh, begitupun dengan gerakan perempuan yang ditandai dengan adanya aksi dari anggota kelompok yang beranggotakan perempuan (umumnya sebagai aktifis) guna menentang ketidakdilan yang dialami kaum perempuan. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan Indonesia masih dijumpai di berbagai aspek kehidupan. Meski secara historis perempuan Indonesia sudah melakukan berbagai aktifitas di ruang publik, seperti berpartisipasi dalam pergerakan nasional melalui berbagai organisasi perempuan, diskriminasi terhadap kaum ini masih tetap ada. Hal itu tampak jelas di era Orde Baru melalui ‘penghentian’ gerakan perempuan yang sudah dirintis oleh kaum ini sejalan dengan pergerakan nasional pada menjelang dan awal kemerdekaan dulu. Bahwa di zaman orde baru atas nama ‘State Ibuism’ aktifitas perempuan Indonesia di ruang publik diatur secara ketat dan cenderung berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki atau suami. Kondisi perempuan yang tersubordinasi ini masih tampak di era Reformasi, pada awal 1999 dan 2000-an, cukup banyak pengambil kebijakan di suatu lembaga menetapkan peraturan yang terkesan membatasi gerak perempuan yang bekerja di sektor publik. Diskriminasi terhadap perempuan ini dapat diihat dari banyaknya peraturan yang ditetapkan pengambil kebijakan di daerah, dalam hal ini para anggota DPRD sebagai pembuat undang-undang yang berkekuatan hukum. Mereka menggunakan kewenangannya dalam membuat peraturan yang didasarkan atas sistem desentralisasi. Reformasi yang diidentikkan sebagai era keterbukaan setelah rezim Soeharto berkuasa secara otoriter selama 32 tahun, ternyata tak serta merta disertai dengan sikap keterbukaan dan demokrasi kepada kaum perempuan. Bahwa Reformasi menghasilkan sistem desentraliasi, salah satu produknya, daerah dipercaya membuat sendiri kebijakan yang terkait dengan kondisi lokal di daerahnya. Hanya saja kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan seperti para anggota Dewan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) cendrung diskriminatif terhadap perempuan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan pemerintah di daerah kabupaten, kota dan provinsi berupa Perda yang cendrung mendiskreditkan dan mengatur ketat aktifitas perempuan di area publik hingga sekarang ini. Data tahun 2013 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 265 dari 342 Perda sebagai produk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Dari 265 Perda diskriminatif, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian, 124 mengatur tentang prostitusi dan pornografi, 27 mengatur pemisahan ruang publik lakilaki dan perempuan dan 35 peraturan terkait dengan pembatasan jam malam bagi perempuan. Semua Perda tersebut tersebar di berbagai Kota, Kabupaten, Provinsi di seluruh Indonesia, kongkritnya tampak pada provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan di beberapa wilayah di Sulawesi. Jumlah Perda diskriminatif itupun mengalami peningkatan; tahun 2011 ada 207 Perda diskriminatif, tahun 2012 berjumlah 282 (Komnas Perempuan, 2013). Menindaklanjuti Perda diskriminatif yang cukup banyak tersebut, hingga tahun 2015 kemarin ini sudah 139 Perda diskriminatif tersebut yang dihapus oleh Mendagri. Penghapusan ini mendapat dukungan dari 144 organisasi perempuan yang bersatu dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam (Paat, 2015). Kajian tentang Perda diskriminatif ini cukup banyak dilakukan, hasilnya berupa pemberitaan, artikel, opini, kritik dan working paper, serta berbagai tulisan dijumpai di media, jurnal dan juga diseminarkan. Kajian tersebut cenderung terkait dengan implementasi pelaksanaan Perda, mengkritisi, menganalisis keberadaan serta jalannya Perda. Candraningrum (2006) secara kritis berpendapat bahwa Perda yang mendiskriminasikan perempuan, disebabkan oleh ketidaktahuan pengambil kebijakan dan pembuat peraturan dalam proses pembuatannya (legal drafting), bahwa adanya 202 pertentangan antara pihak yang pro-kontra dengan Perda tersebut adalah karena beda interpretasi tentang syariah dan ajaran agama Islam. Kajian Robyn Bush (2008) bahwa Perda Syariah terkait dengan symbol agama dan sikap religious di aras lokal. Kajian bersifat lokal tentang Perda di Sumatera Barat oleh Wibowo (2007) mengenai busana muslimah sebagai produk peraturan di Kabupaten Solok yang dianalisis dalam perspektif hukum Ketatanegaraan. Dibanding dengan Perda, kajian tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang bersifat lokal dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan masih terbatas. Rancangan yang masih berupa embrio, cikal bakal peraturan yang akan ditetapkan bisa dihalangi menjadi sebuah peraturan bila ada tekanan dan desakan dari pihak tertentu untuk menghentikan proses pembuatannya. Desakan dan tekanan dari grup atau kelompok yang prihatin dengan ketidakadilan terhadap perempuan ini tampak dari kegiatan organisasi jurnalis perempuan di Sumatera Barat (FKWIS-Forum Komunikasi Wartawan Perempuan Suntiang Nagari). FKWIS melakukan berbagai upaya dalam rangka menolak Ranperda yang salah satu klausulnya berisi larangan bagi perempuan keluar malam lewat dari jam 10 hingga jam 6 pagi bila tanpa ada muhrim yang menemani. Tidak mudah memang mengatakan aktifitas FKWIS dalam menolak Ranperda ini sebagai suatu gerakan perempuan, tapi setidaknya adanya upaya kelompok organisasi perempuan ditingkat lokal dengan identitas jurnalis-nya bergerak membela kaumnya. Dengan demikian menjadi relevan untuk mengkaji gerakan kelompok perempuan dalam sebuah organisasi untuk menghentikan adanya Perda diskriminatif tersebut. Mengingat pentingnya mengantisipasi keberadaan Perda yang diskriminatif , maka tulisan ini menggali lebih jauh; Bagaimana upaya dan proses perlawanan organisasi perempuan jurnalis di Sumatera Barat (FKWIS) dalam usaha mengkritisi Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memiliki klausul mendiskriminasikan perempuan yang bekerja di sektor publik?. Bagaimana FKWIS sebagai organisasi mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menghentikan Ranperda menjadi Perda?. Tujuan penelitian ini mengungkapkan proses kegiatan FKWIS selaku organisasi lokal di Kota Padang, Sumatera Barat di awal era Reformasi, organisasi ini aktif menentang Ranperda diskriminatif tersebut. Selanjutnya, agar gerakan sosial yang dilakukan FKWIS bisa menginspirasi organisasi perempuan di kota atau kabupaten lainnya menolak Ranperda dan Perda lokal yang bersifat diskriminatif. Diharapkan dengan mengungkapkan aktfitas jurnalis perempuan ini ada manfaatnya untuk dijadikan contoh dan pembanding bagi organsasi lainnya dalam upaya mengurangi Perda dan Ranperda diskriminatif melalui membaca dan mengetahui strategi yang digunakan FKWIS. 2. Tinjauan Pustaka Studi tentang gerakan sosial (Social movement) dianggap penting dalam menganalisa dan memahami fenomena sosial ditengah masyarakat, karena gerakan sosial dapat menjelaskan fenomena apa yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau, bagaimana proses hingga bisa terjadi, sehingga bisa memiliki strategi dan pemahaman dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini. Jadi dalam gerakan sosial ada sejumlah harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik (Sztompka, 2007). Meski defenisi gerakan sosial cukup banyak, setidaknya defenisi yang berbeda-beda itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek seperti dikatakan McAdam & Snow (1997: xviii) bahwa gerakan sosial dapat ditandai dengan adanya; (1) Aksi bersifat kolektif, (2) Tujuan untuk perubahan sosial, perubahan struktur atau perubahan peraturan, (3) Organisasi sebagai wadah gerakan, (4) Kesinambungan gerakan dalam masa waktu tertentu, (5) Beberapa kombinasi aksi bersifat internal dan eksternal seperti protes di jalanan dan loby. Aspek- 203 aspek yang demikian ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh FKWIS sebagai sebuah organisasi di tahun 2001 dalam usaha menolak Ranperda. Gerakan sosial, menurut McAdam, McCarthy, Zald (1997) dilihat dalam tiga perspektif; political opportunities, framing process dan resource mobilization. Perspektif Resource mobilization atau mobilisasi sumber daya fokus pada kemunculan gerakan sosial terkait dengan mobilisasi dalam level struktural, dimana adanya sejumlah sumber-sumber yang bisa dan memiliki potensi untuk digerakkan demi mencapai tujuan gerakan sosial; sumber tersebut antara lain jumlah anggota, yang memiliki sumber daya dan potensi. Dalam konteks FKWIS, adalah organisasi berbasis perempuan dan berprofesi sebagai jurnalis; anggotanya sebagai wartawati memiliki kesempatan menggunakan medianya sebagai sarana mencapai tujuan. Sebagai pekerja media, FKWIS memiliki kapasitas dan memiliki jaringan, kenalan yang bisa diajak berkoordinasi, bekerjasama melakukan gerakan perlawanan membatalkan pasal Ranperda yang diskriminatif. Aktifitas dan kesadaran perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan tak terlepas dari pengalaman perempuan itu sendiri. Sepanjang sejarahnya gerakan protes yang dilakukan perempuan (women’s movement) menurut West dan Blumberg (1990: 13) dilakukan atas dasar empat isu utama yakni; (1) terkait langsung dengan kondisi ekonomi untuk bisa bertahan hidup, (2) berhubungan dengan perjuangan etnis, grup dan sikap nasionalisme, (3) berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan (4) terkait dengan hak azazi dan persoalan perempuan. Dalam konteks gerakan FKWIS, Ranperda yang menyatakan pelarangan bagi perempuan untuk keluar malam dianggap melanggar hak azazi perempuan, karena gerak mereka yang dibatasi. Hal ini berakibat pada pilihan pekerjaan, perlindungan kerja dan kepastian hukum bagi kaum perempuan yang terkena peraturan Ranperda tersebut. Dalam agenda kegiatannya, FKWIS juga melakukan penguatan kepada para anggotanya. Oleh karena itu, kiprah FKWIS ini dapat diuraikan juga melalui teori identitas kelompok. Dikatakan Taylor and Whittier (1992), konsep tentang identitas kelompok bisa dilihat pada tiga aspek; adanya (1) Batasan antara kelompok dominan dan kelompok yang melawan dominasi; batasan terbentuk secara sosial, psikologi dan fisik, (2) Kesadaran berupa penafsiran anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka (3) Adanya negosiasi yang meliputi symbol dan aksi untuk meruntuhkan kelompok dominan yang mapan. Dalam konteks berdiri dan eksisnya FKWIS, ketiga aspek tersebut dapat dijumpai; bahwa kesadaran para jurnalis perempuan tentang perlunya lembaga untuk berkumpul dan bersatu dalam menghadapi kelompok dominan yang melakukan perbedaan perlakuan pada jurnalis perempuan. Sumatera Barat sebagai basis penelitian ini, memiliki sistem matrilineal. Yakni sistem yang menurut garis keturunan ibu, pewarisan harta pusaka didasarkan garis ibu. Sistem ini meninggikan dan menghargai posisi perempuan senior di tengah keluarga besar, dan diwujudkan dalam sebutan Bundo Kanduang. Sistem ini setidaknya telah mempengaruhi pola berpikir perempuan Minangkabau, bahwa perempuan sebagai Bundo Kanduang, sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang semestinya memiliki keterampilan hidup dan kemampuan untuk menjalankan perannya di dalam keluarga besarnya. Itu artinya perempuan Minang hendaknya mampu bersikap bijaksana, adil dan memahami kebutuhan anggota keluarga besarnya. Oleh karena skill hidup hanya bisa didapatkan melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan, maka tak heran bila dari sejak zaman dulu perempuan Minang diizinkan untuk mendapatkan porsi pendidikan yang sama seperti halnya anak laki-laki. Maka tak heran bila sejak awal abad 20 sudah ada perempuanperempuan Minang yang berkiprah di sektor publik seperti Roehana Koeddoes dan kawankawannya (Sa'adah Alim, Zahara Ratna Djoewita Sjamsidar Jahja) Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah, Sitti Manggopoh, Zakiah Darajat dan lainnya. Dalam perkembangannya, 204 nama-nama tersebut adalah perempuan-perempuan Minangkabau yang sudah berkiprah di sektor publik yang memiliki kebebasan berpikir, kreatif dan bermanfaat bagi orang banyak jauh sebelum Indonesia merdeka. 3. Metode Penelitian Penelitian ini berlokasi di Kota Padang Sumatera Barat. Padang sebagai Ibukota Provinsi merupakan pusat pemerintahan provinsi dengan berbagai dinamika politik lokal dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat provinsi. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya penelitian tentang upaya organisasi FKWIS melawan Ranperda diskriminatif, yang home-base nya berada di Padang seperti halnya para anggota DPRD provinsi selaku pembuat Ranperda berkantor di Kota Padang. Penelitian menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif untuk mendapatkan detail data lisan dari orang dan prilaku yang diamati secara utuh dan terperinci. Dalam konteks penelitian ini untuk mendapatkan info detail proses mobilisasi sumber daya yang dimiliki FKWIS, dan proses negosiasi dengan pengambil kebijakan dalam upaya menolak Ranperda yang mendiskriminasikan perempuan. Untuk mendapatkan data lisan tersebut, peneliti menjadikan individu sebagai unit analisis. Populasi dan sampling dalam penelitian ini adalah para anggota FKWIS, Ketua FKWIS, pihak komisi E DPRD Provinsi Sumbar periode 1999-2004 serta Bundo Kanduang, sebagai pemuka dan tokoh masyarakat Sumbar mewakili kaum perempuan di Sumbar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dimungkinkan karena peneliti pada saat itu (tahun 1999-2003) dalam kapasitas anggota FKWIS, sedangkan wawancara bersifat mendalam dilakukan kepada para informan. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling atau informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan . Analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan dilakukan dengan menggunakan berapa tahapan; mulai dari mereduksi data dengan memilah, mensortir data yang sudah dikumpulkan melalui indepth interview dan observasi, lalu mengelompokkannya menjadi tema yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian data diinterpretasikan, dilakukan sintesa dari temua data sehingga menjadi sistematis untuk dibaca dan dipahami. 4. Temuan dan Pembahasan Dari penelitian terungkap adanya sejumlah temuan yang menunjukkan adanya mobilisasi sumberdaya organisasi FKWIS. Berikut uraiannya; 1. FKWIS: Kemunculan, Identitas dan Penguatan Anggota Dari kenyataan di lapangan, keberadaan FKWIS tak lepas dari dinamika jurnalistik di Sumatera Barat. Sebelum Reformasi jumlah media tak banyak; 3 koran harian dan 1 mingguan, tapi setelah 1998 sejalan dengan pergantian pemerintahan, ditandai dengan demokrasi dan kebebasan pers. Alhasil dalam kurun waktu empat tahun; 1998-2002 terdapat 39 surat kabar di Sumatera Barat, namun yang bertahan hingga 2003 ada 15, 24 lainnya tidak terbit (Eska, 2003). Konsekuensi dari banyaknya media, tentulah membutuhkan pekerja media yang cukup banyak pula, maka berlombalah semua pencari kerja di era krisis moneter ketika itu berebut lahan, termasuk juga yang perempuan, berminat bekerja di bidang jurnalistik, umumnya sebagai peliput berita di lapangan atau reporter. Tak semua bisa bertahan seperti media yang juga tiba-tiba hilang, namun adalah suatu fakta nyata berdasar observasi dan pengalaman bahwa jurnalis perempuan jumlahnya bertambah dibanding era Orde Baru. 205 Semakin banyaknya pelaku jurnalis perempuan, dengan segala dinamikanya sebagai pihak yang seringkali mendapat perlakuan berbeda dalam menjalankan profesi, mendorong mereka untuk saling tukar pengalaman. Kondisi ini jadi momen tepat untuk berkumpul dan saling berkomunikasi. Adanya kesadaran jurnalis perempuan untuk saling berbagi informasi dan menguatkan, mendorong mereka membentuk satu wadah bagi jurnalis perempuan di Sumatra Barat. Seperti terungkap dalam wawancara dengan Ketua FKWIS terpilih ketika itu, Dra. Imiarti Fuad dari TVRI Sumbar dan juga ditulis Eska (2003), bahwa pada 5 Mei 1998, para perempuan jurnalis, dimotori oleh Frislidia, SH (Jurnalis di LKBN Antara), Ir.Atviarni dan Ir. Rina Moreta (Singgalang), Altasia, Ir. Fitri Adona, M.Si and Sri Taufik (Semangat), Husnul Rais (Haluan), Nita Indrawati Arifin (Majalah Kartini) sepakat membentuk organisasi yang mereka sebut FKWIS Suntiang Nagari- “Forum Komunikasi Wartawati Sumatera Barat, Perempuan Nagari”. Dapat dikatakan bahwa pembentukan organisasi ini tak terlepas dari latar belakang sejarah jurnalistik di Sumatera Barat jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahwa wartawati pertama di Indonesia, Roehana Koeddoes, berasal dari daerah ini. Bersamasama dengan perempuan aktifis lainnya, Zahara Ratna Djoewita, Roehana telah mampu mengelola dan memimpin surat kabar ‘Soenting Melayu’ (Fitriyanti,2001). Surat kabar ini pertama kali terbit pada 10 Juli 1912, fokus pada isu perempuan dan telah berjuang untuk mencerdaskan kaumnya lewat surat kabar yang mereka kelola. Jadi keberadaan wartawati pertama di Sumatera Barat dengan media yang dikelola perempuan lebih seratus tahun lalu itu, menginspirasi para anggota FKWIS untuk kembali menggiatkan semangat jurnalistik perempuan dan memberdayakan kaum perempuan di Sumatera Barat. Mengutip istilah yang disebutkan Eska (2003) “Mambangkik batang tarandam”, dapat dikatakan bahwa keberadaan FKWIS, karena adanya kesadaran berpikir bahwa secara historis, perempuan di Sumatera Barat sudah berbuat untuk kaumnya, sudah berkiprah di area publik sejak lebih seratus tahun lalu, maka sekarang pun harus dimunculkan kembali. Situasi yang demikian sesuai dengan konsep identitas kelompok seperti dikatakan Taylor dan Whittier; bahwa ada batasan, kesadaran dan negosiasi. Batasan bahwa mereka sebagai jurnalis perempuan diperlakukan berbeda oleh perusahaan tempat bekerja; bahwa ini bagian yang bisa diliput jurnalis perempuan dan ada area rawan (menurut atasan media )dan tak perlu diliput jurnalis perempuan; bahwa wartawan perempuan cukup sampai jam 8 di kantor dan lakilaki bisa lebih malam lagi. Terkait dengan batasan bidang kerja dan pembedaan perlakuan, dengan secara sadar mereka bersatu dalam organisasi atas nama identitas kelompok wartawan perempuan. Lalu diinspirasi dari keberadaan wartawan perempuan pertama dengan kiprahnya mengelola surat kabar untuk kepentingan perempuan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dari wawancara dengan Ketua FKWIS, diketahui bahwa keberadaan organisasi untuk melindungi anggota (sesama wartawati) dari perlakuan diskriminasi. Hal ini karena ada kecendrungan area kerja jurnalis perempuan hanya ditugaskan meliput berita bersifat seremonial, soft news dan tidak banyak resiko serta tantangan. Sebaliknya jurnalis laki laki dapat sepenuhnya bekerja pada berbagai area liputan, bisa ke luar kota yang butuh waktu seharia bahkan lebih dan itu oleh pimpinan media dianggap melelahkan, tak sesuai dengan kondisi fisik perempuan. Selain itu FKWIS memiliki tujuan untuk membuat pemberitaan yang tidak mendiskreditkan perempuan selaku obyek pemberitaan semisal berita perkosaan dan razia PSK; Kecendrungan yang sering dijumpai di banyak media atau surat kabar, berita perkosaan atau razia PSK terkesan mengabaikan hak azazi perempuan selaku korban perkosaan dan melecehkan perempuan yang menjadi obyek pemberitaan. Ini dapat dimaklumi lantaran persaingan ketat media sehingga untuk memenuhi selera pembaca dan agar koran laku terjual berita yang ditulis kadang menyudutkan perempuan yang jadi korban. 206 Untuk itulah FKWIS berusaha menyajikan pemberitaan yang lebih sensitif gender serta memberikan penyadaran gender melalui tulisan yang mereka tulis. Advokasi terhadap para anggota FKWIS tetap berlangsung, terutama sekali jurnalis perempuan yang mendapat perbedaan perlakuan. Seperti dialami salah seorang informan yang kantornya menetapkan aturan jurnalis perempuan hanya bertugas hingga pukul 8 malam saja; bahwa ia tetap bertahan hingga lewat jam 8 malam di kantor, sebagian dari koleganya, jurnalis laki-laki tidak memasalahkan hal tersebut, sementara sebagian lagi ada yang komplain atas pelanggaran aturan tersebut. Ketika dikomunikasikan situasi kantor tersebut kepada pihak FKWIS, jurnalis ini mendapat dukungan untuk tetap bertahan di kantor meski lewat jam 8 malam guna menyelesaikan tulisan atau tugas yang diembankan atasan kepadanya. “Bukti dukungan kami dari FKWIS yakni dengan mengantarkan si jurnalis perempuan ini pulang ke rumahnya, kami jemput ke kantornya kemudian dengan alat transportasi yang kita punya diantar pulang ke rumah” (wawancara dengan Ketua FKWIS). Apa yang telah dilakukan ketua FKWIS dengan memberi dukungan untuk tetap bekerja di kantor meski lewat dari jam 8 malam, dibuktikan dengan memberikan bantuan jasa transportasi pulang diantar pihak FKWIS. Ini menunjukkan bahwa organisasi mereka berusaha melindungi anggota kelompoknya, sebagai bentuk solidaritas lantaran memiliki identitas yang sama. Mereka, sesama jurnalis dari media yang berbeda, biasanya dalam konteks pekerjaan, media berbeda saling bersaing untuk mendapatkan isu berita terbaik, dan adakalanya terbawa dalam proses pencarian berita. Namun karena sama sama didiskriminasi, kesamaan mendapat perlakuan berbeda yang diterima dari pimpinan media, tak ada bentuk persaingan tersebut. Sebaliknya bersatu, saling tolong menolong, mendukung para anggotanya untuk terbebas dari perbedaan perlakuan, seperti yang dialami kolega mereka dimana tempat ia bekerja melarang pulang lewat dari jam 8 malam. Di satu sisi dapat dimaklumi adanya kebijakan tak boleh pulang larut malam bagi perempuan, karena dunia jurnalistik dianggap dunia keras, yang pekerjanya lebih banyak laki-laki dan dengan alasan keamanan, pekerja perempuan disegerakan pulang bila telah lewat maghrib, sebab kantor tak mau repot bila terjadi apa-apa dengan pekerja perempuannya. Namun di sisi lain pemberian kesempatan kepada perempuan yang juga memiliki kapasitas di bidang jurnalistik adalah perlu. Bila jurnalis perempuan merasa masih perlu menulis berita, mempersiapkan materi dan bahan liputan untuk besok, atau yakin dengan kemampuannya untuk meliput tentang isu politik; kampanye, partai politik dan petinggi parpol atau pejabat pusat yang datang ke daerah, dan merasa mampu meliput di luar kota Padang yang butuh waktu lama dan melelahkan, pembatasan dan perbedaan ini menjadi persoalan. Bahwa mereka telah mengalami hambatan sewaktu bekerja dan berkreatifitas. Itu artinya mereka telah didiskriminasikan. Pendiskriminasian yang seperti ini, selanjutnya telah mendorong dan memicu FKWIS dan para anggotanya untuk kritis dan menentang bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan, salah satunya melalui penolakan terhadap Ranperda yang salah satu pasalnya (pasal 10 ayat 3) terdapat klausul melarang perempuan melakukan aktifitas di atas jam 10 malam bila tak didampingi oleh murimnya. 2. Gerakan FKWIS Melawan Ranperda Ranperda Pekat (Pelarangan Perbuatan Maksiat), demikian nama Ranperda yang dibuat oleh komisi E DPRD Provinsi Sumbar. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, Ranperda Pekat yang mulai dibuat pada pertengahan Maret 2001 itu merupakan salah satu implementasi dari kewenangan daerah menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Pasal 10 ayat 3 Ranperda Pekat tersebut berbunyi: “Setiap Wanita dilarang berada di luar rumah di atas jam 22.00 malam sampai jam 06.00 pagi, kecuali dengan muhrimnya”. 207 Klausul yang demikian inilah yang menjadi pokok masalah sebenarnya, karena dari pasal tersebut, ada kesan kalau pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Sumatera Barat seolah akan menyelesaikan persoalan maksiat yang memang cukup rumit diatasi, dan ini menggambarkan perempuan sebagai pangkal persoalan maksiat. Jelas ini merendahkan dan melukai kaum perempuan dan sangat bertentangan dengan pengakuan hak azazi manusia secara internasional, seperti tercantum dalam pasal VII Civil Right Act tentang anti pendiskriminasian. Lebih dari itu pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 juga sudah ikut meratifikasi Convention on the Elimination of All Types of Discrimination against Women (CEDAW). Itu artinya Negara Indonesia melalui pemerintahnya turut serta menghormati hak setiap individu dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminasi yakni, tidak membedakan ras, suku, agama, kelas sosial, bahasa dan jenis kelamin (Sadli, 2012). Pertentangan antara penghormatan terhadap hak azazi manusia yang anti diskriminasi dengan adanya pasal diskriminatif dalam rancangan peraturan yang demikian telah mendorong FKWIS untuk melakukan gerakan perlawanan. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan agar Ranperda yang didalamnya ada pasal diskriminatif itu dihapuskan. Diantara upaya membatalkan pasal diskriminatif tersebut; membentuk opini public melalui dialog interaktif, talk show dan pooling, melakukan dialog dan diskusi dengan pihak pembuat Ranperda, menggelar seminar dengan menghadirkan narasumber tingkat nasional, berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya (roundtable discussion). Berikut diuraikan lebih detail kegiatan dan gerakan FKWIS lakukan: a). Membentuk Opini Publik Dari hasil temuan di lapangan, diketahui bentuk perlawanan menolak Ranperda diskriminatif dengan membentuk opini publik melalui kegiatan dialog interaktif, talk show dan polling atau survei pendapat. Hampir setiap hari dari April 2001 hingga Juni 2001 ditampilkan acara talk show atau dialog interaktif antara audiens (pendengar dan penonton) yang diselenggarakan oleh produser TVRI perempuan dan programmer radio perempuan dengan topik utama terkait dengan adanya rencana aturan pelarangan perempuan keluar malam. Topik dialog tak lepas dari isu perempuan, pemberdayaan dan pencapaian yang telah dilakukan perempuan dalam karirnya disektor publik. Misi utama dari setiap dialog dan talk show tersebut adalah menyelipkan isu tentang pembatasan perempuan beraktifitas lewat jam 10 malam seperti yang bakal diatur dalam Perda. Sesuai dengan tema dialog, dihadirkan narasumber yang variatif, mulai dari pihak perumus Ranperda (Ketua Komisi E DPRD Sumbar periode 1999-2004, Khaidir Khatib Bandaro), pemuka masyarakat, unsur budaya dan aktifis perempuan. Salah satunya Bundo Kanduang Sumatera Barat, Puti Reno Raudha Thaib. Dalam salah satu talk show marathon tersebut, diungkapkan oleh Bundo Kanduang bahwa di satu pihak, sejak dahulunya kebiasaan di masyarakat Minang sudah membolehkan perempuannya untuk bersekolah tinggi, memiliki ilmu pengetahuan dan berkiprah di luar rumah dan di pihak lain pengawasan terhadap perempuan Minang juga perlu. Namun juga suatu kesalahan bila untuk mengontrol perempuan Minang dengan membuat generalisasi bahwa untuk mengawasi kasus prostitusi dan masalah sosial yang banyak muncul sekarang ini dengan cara melarang perempuan untuk berkegiatan di luar rumah. Materi dan proses dialog interaktif dan talk show itu secepatnya diberitakan para wartawati di berbagai media cetak tempat mereka bekerja. Salah seorang pendiri FKWIS dalam kapasitasnya sebagai broadcaster di sebuah radio, Wirnita Eska, mengadakan 208 pooling pendapat warga kota Padang tentang pelarangan perempuan untuk keluar malam melalui SMS. Setiap pendengar diberi kesempatan mengirim pendapat mereka dengan mengirim SMS ke nomor yang telah ditetapkan, kemudian dibacakan ketika sedang siaran. Diketahui, pendapat warga kota lebih banyak yang menolak Ranperda berisi pasal pembatasan keluar malam itu. Gencarnya usaha melawan pasal yang diskriminatif tersebut diberitakan oleh media nasional bahkan oleh BBC London. Ketua FKWIS, Imiarti Fuad dihubungi BBC London perwakilan Jakarta dan diinterview sehubungan dengan alasan menentang pasal diskriminatif tersebut. Seperti dikatakannya: “…Aku ngga ingat lagi siapa nama interviewernya dan aku sempat kaget karena darimana dia tahu nama dan HP ku, tapi katanya dari wartawan juga dia tahu dan aku diwawancarai kenapa aku dan kawan-kawan tergerak untuk menentang Ranperda itu...Ya aku jawab aku terlahir sebagai perempuan minang dan aku merasa punya tanggungjawab untuk mengangkat dan mempertahankan harga diri perempuan minang, aku juga tidak mau perempuan minang generasi mendatang dirugikan dengan aturan yang diskriminatif begitu. Emang kita ngapain kalau keluar rumah pada jam begitu, apa semua perempuan minang kalau keluar jam segitu mau jual diri? Bagaimana kalau ada perempuan yang harus kerja di malam hari, apa dia harus dihukum dengan aturan itu? Bagaimana kalau seorang anggota DPRD perempuan harus rapat di malam hari atau bagaimana kalau seorang direktris dan profesional terpaksa harus menyelesaikan tugasnya di malam hari atau seorang wartawati kerja sampai malam karena mengejar deadline, so apa kami harus ikuti aturan yang begitu…?” (Wawancara via email, 24 November 2005). Dari apa yang disampaikan pimpinan organisasi dan dari berbagai usaha yang sudah mereka lakukan di atas, tampak adanya saling bekerja sama para jurnalis perempuan dalam usaha menciptakan opini publik. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan menyiarkan dan memberitakan proses dialog interaktif dan talk show, kemudian menuliskan beritanya di berbagai media tempat mereka bekerja. Sebagai pekerja media, dalam upaya tersebut, mereka juga berusaha seobjektif mungkin untuk memperoleh pendapat dari seluruh lapisan masyarakat melalui pooling yang membebaskan masyarakat untuk berkomentar. Juga dalam pemilihan narasumber dialog, berasal dari latar belakang yang bervariasi atau dari kedua pihak yang pro dan kontra. b). Berkomunikasi dan Berjejaring Selain menciptakan opini publik, berkomunikasi secara intens dan membuat jaringan dengan sesama organisasi perempuan adalah hal penting yang mendukung mereka untuk menggolkan tujuan pembatalan pasal di Ranperda. Melalui diskusi reguler dari Maret 2001 sampai May 2001, para anggota FKWIS mengadakan pertemuan, saling diskusi, bertukar informasi, pendapat dan ide. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dari anggota, sekaligus mengatur srategi yang akan dilakukan agar tujuan mereka atas tuntutan penghapusan pasal diskriminatif bisa terlaksana. Kegiatan diskusi dilakukan setiap hari Jumat mulai jam 4 sampai jam 6 bertempat di kantor FKWIS. Mereka menyebutnya diskusi Jumat sore. Selain para anggota FKWIS, turut diundang organisasi perempuan lainnya guna menginformasikan kondisi terkini dan mendengarkan pendapat mereka. Hal yang paling difokuskan dalam pertemuan dua jam itu adalah kesamaan suara para organsasi perempuan yang diundang, bahwa Pasal 10 ayat 3 dalam ranperda diskriminatif dan sangat merendahkan kaum perempuan. Dari hasil diskusi yang rutin tersebut, kemudian disepakati mengirim petisi untuk disampaikan ke Komisi E 209 DPRD Sumbar. Petisi yang ditanda tangani pada Rabu, 16 May 2001 ditandatangani oleh lima orang Ketua organisasi perempuan diantaranya Ketua FKWIS, LP2M, KPI Sumbar, dan LSM Mande serta Naluri Perempuan. Beberapa hari setelah mengirim petisi ke pihak DPRD Sumbar, FKWIS dan beberapa organisais perempuan lainnya itu diundang ke DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing). c). Dialog dan Diskusi dengan Tim Perumus Dalam berbagai kesempatan FKWIS berusaha untuk melakukan pendekatan dialog dengan tim perumus Ranperda, yakni para anggota Komisi E DPRD Sumbar. Puncaknya setelah mengajukan petisi, mereka diharapkan hadir di Gedung Rakyat secara resmi dalam rapat dengar pendapat (hearing) pada Selasa, 29 May 2001. Dalam dialog dengar pendapat tersebut, pihak FKWIS dan rombongan yang menandatangani petisi, berjumlah 8 orang tetap bersikukuh pada apa yang menjadi tuntutan mereka. Agar pasal yang mendiskriminasikan perempuan dihapus. Dalam Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi E ketika itu, Khaidir Khatib Bandaro, menyampaikan argumentasi mereka yang merumuskan draft tersebut, bahwa alasannya adalah karena untuk mengatasi masalah maksiat di Sumatera Barat dan untuk menjaga, marwah, kehormatan perempuan Minang. Menanggapi pernyataan Ketua Komisi E, pihak FKWIS tetap pada argumen mereka bahwa penerapan pasal tersebut sangat tidal adil bagi perempuan. Bila pasal itu diberlakukan akan menghambat kreatifitas, pengetahuan dan kemampuan perempuan, karena tak semua perempuan yang beraktifitas malam hari perempuan yang takbaik, justru sebaliknya masih banyak perempuan dengan berbagai profesi yang akan terkena pasal tersebut. Selama 4 jam pertemuan rapat dengar pendapat tersebut, adu argumentasi itu diakhiri dengan ketegasan pihak FKWIS. Seperti diungkapkan Ketua FKWIS bahwa yang diinginkan dalam gerakan mereka sebenarnya adalah menghapuskan pasal diskriminatif tersebut, bila tidak juga, maka agar adil, kata perempuan yang diubah, seperti dikatakan; “….Yang kami tuntut hanya jangan ada kata perempuan Sumatera Barat di klausul itu, solusinya gantilah dengan setiap orang Sumatera Barat atau siapapun, kalau memang klausul itu harus tetap dilanjutkan....jadi adil kan.....”. (Wawancara dengan Ketua FKWIS) d). Menggelar Seminar Guna mendapatkan lebih banyak lagi dukungan, FKWIS mengadakan seminar nasional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya; Dr. Dewi Fortuna Anwar (ahli politik bekerja di LIPI), Dr, Chandra Motik (ahli hukum), Debra Yatim (aktifis perempuan) dan Dr. Hayati Nizar (mewakili Komisi Perempuan dan Keluarga MUI Sumbar). Seminar yang diadakan Sabtu, 2 Juni 2001 di Pangeran Beach Hotel itu menghadirkan banyak peserta dan berusaha membuka mata para peserta dan undangan yang hadir tentang Ranperda Pekat tersebut. Bahwa keberadaan Ranperda dnegan pasal 10 ayat 3 yang diskriminatif itu pertanda adanya 'kecolongan intelektual' dan pemaksaan secara tidak langsung kepada perempuan dalam menghambat aktifitas dan kreatifitas mereka. Bahkan Dr. Hayati Nizar memberikan catatan kritisnya tentang keberadaan pasal diskriminatif tersebut seperti dikutip dalam Eska (2003:137-138); (1) Adanya penggeneralisasian bahwa semua perempuan cenderung nakal hingga haris diberlakukan jam malam dimanapun mereka berada, (2) Bisa dipertentangkan dengan HAM karena telah adanya pembatasan terhadp semua perempuan, termasuk perempuan baik-baik, (3) Adanya anggapan seoah-olah budaya kontrol tidak ada lagi di masyarakat sumatera Barat sehingga harus ada Perda yang mengatur. 210 Usai seminar, pada malam hari masih dilanjutkan pertemuan antara pihak FKWIS dan para narasumber. Pertemuan informal tersebut sekali lagi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari para ahli tersebut dan bersama-sama mereka satu tujuan melawan pasal yang diskriminatif tersebut. 3. Mobilisasi Sumber Daya Hapuskan Pasal Diskriminatif Dapat dimaklumi bila setiap pengambil kebijakan di daerah memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakatnya, termasuk para perempuannya, karena masing-masing daerah yang masih kental budaya dan ikatan agamanya memiliki batasan tersendiri terhadap perempuannya. Hal demikian diimplementasikan oleh pengambil kebijakan di tingkat lokal dalam bentuk peraturan mengikat, namun ada diantaranya berupa Perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Sebelum menjadi Perda tentunya ada proses pembuatan dan mendiskusikan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hanya saja dalam proses pembuatan draft rancangan oleh Komisi E DPRD Sumbar ada draft yang dinilai sangat diskriminatif. Dalam proses mengantisipasi Ranperda menjadi Perda inilah FKWIS memainkan perannya. Yakni dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk menginformasikan dan memberitahu khalayak bahwa apa yang sedang direncanakan pengambil keputusan, membuat Perda akan berakibat tidak baik bagi perempuan di Sumatera Barat. Kegiatan penciptaan opini publik seperti berupa dialog interaktif, talk show, pooling sms dan seminar itu sangat mungkin dilakukan karena mereka adalah para jurnalis. Sebagai jurnalis mereka memiliki sarana dan prasarana media sebagai alat dan wadah menyampaikan gerakan mereka. Agaknya apa yang sudah dilakukan FKWIS tersebut sejalan dengan teori mobilisasi sumber daya, seperti dikatakan oleh McCarty dan Zald (1979:vii), bahwa pendekatan mobilisasi sumber daya menekankan adanya rasa tidak puas satu kelompok yang melakukan gerakan dengan fokus pada dukungan masyarakat, tekanan kelompok dalam gerakan , kendali sosial dan penggunaan media. Jadi dari apa yang telah dilakukan FKWIS melalui dialog interaktif, talk show,menulis berita di media massa, dan mengadakan polling sms, mengadakan seminar sebagai usaha untuk memberikan informasi dan membuka mata masyarakat dengan tujuan agar diketahui bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan isu yang mereka lemparkan. Kegiatan tersebut dilakukan secara intens dalm rentang waktu yang singkat, sehingga target mereka agar khalayak umum bisa tahu perkembangan terakhir dan langkah atau proses yang sedang berlangsung terkait dengan pasal diskriminatif. Dengan demikian, update informasi yang dilakukan dalam gerakan ini langsung diketahui oleh publik, pengikut isu ini tentang apa yang telah dan sedang diperbuat oleh pihak pengambil kebijakan. Juga untuk mengetahui negosiasi pihak FKWIS dan organisasi lainnya sekaitan dengan pasal yang dituntut untuk dihapuskan tersebut. Selain penggunaan media (media usage), dukungan sosial (societal support) juga telah diupayakan oeh FKWIS melalui jalinan komunikasi dan membuat network dengan organisasi perempuan, aktifis perempuan, tokoh perempuan lainnya. Mereka intens mengadakan pertemuan, diskusi, bersepakat membuat petisi. Ini menunjukkan mereka memiliki koordinasi dan langkah yang sama sehingga tujuan yang sama-sama mereka citakan, yakni penghapusan pasal diskriminatif, pasal 10 ayat 3 dapat tercapai. Para tokoh perempuan level nasional juga diinformasikan dan dilibatkan dalam gerakan yang sedang mereka lakukan dan melobi mereka agar mendapat dukungan. Pada akhirnya apa yang sudah dilakukan untuk menolak pasal diskriminatif itu berhasil. Itu semua hasil kombinasi dari menngerakkan semua potensi yang dimiliki anggota FKWIS dan dengan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya. 211 5. KESIMPULAN Diskriminasi terhadap perempuan tanpa disadari juga turut terbawa dalam zaman Reformasi, seperti yang dialami oleh para pekerja media perempuan di Sumatera Barat. Meski kran demokrasi sudah dibuka seluasnya yang dibuktikan dengan banyaknya berdiri organisasi politik (partai politik), media cetak dan online, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta NGOs, itu semua tak menjamin akan adanya penghormatan terhadap hak azazi manusia (HAM) dan anti diskriminasi. Untuk itulah FKWIS melakukan gerakan perlawanan atas ketidakadilan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Sumber daya yang dimanfaatkan organisasi FKWIS berasal dari dalam organisasi (sumber daya internal) dan dukungan lingkungan sosial sekitar. Sumber internal dalam hal ini kapasitas dan potensi anggota., atau berasal dari luar organisasi seperti dukungan lingkungan sekitar dan jaringan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks gerakan yang dilakukan oleh FKWIS, sejumlah sumber daya yang dimiliki anggota kelompok sebagai jurnalis dimanfaatkan demi mencapai tujuan dalam menentang Ranperda diskriminatif. Yakni dengan membuat berita terkait isu pasal diskriminatif, mengadakan dialog interaktif, talk show, dan polling sms demi membentuk opini publik. Begitupun dengan potensi kepemilikan jaringan berupa hubungan baik dengan pihak di luar organisasi menjadi modal untuk melakukan aktifitas guna mencapai tujuan organisasi mereka. 6. DAFTAR PUSTAKA Candraningrum, Dewi. 2006. “Perda Sharia and the Indonesian Women’s Critical Perspectives”, Working paper on SOAI (Suedostasien Informationsstelle, Asienhaus) and MATA Asien in Blick, at ÜBERSEEMUSEUM Bremen, Germany Eska, Wirnita. 2003. "Perempuan Minang dalam Membangun Kekuatan melalui Media Massa." Jurnal Perempuan 28: 131-141. McAdam, Doug and Snow, David A. (Ed).1997.Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics. Los Angeles: Roxbury Publishing Company. McCarthy, John D, and Zald, Mayer N, (1997) “Resources Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.” American Journal of Sociology 82: 12-41. Paat, Yustinus. 2015. "Gerakan Indonesia Beragam Dukung Mendagri Hapus 139 Perda Diskriminatif." Berita Satu.com, diakses 24 April 2016, http://www.beritasatu.com/nasional/300049-gerakan-indonesia-beragam-dukungmendagri-hapus-139-perda-diskriminatif.html. Sadli, Saparinah. 2012. Berbeda tetapi Setara Pemikiran tentang Kajian Perempuan. Jakarta: Kompas. Sztompka, Piotr. 1993. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Taylor, Verta and Nancy E.Whittier. 1992.. “Collective Identity in Social Movement Communities; Lesbian Feminist Mobilization”. Frontiers in Social Movement Theories: 104-129. West, Guida and Blumberg R Louis (Ed).1990. Women and Social Protest. New York: Oxford University Press. ---------------. 2013. "Komnas Perempuan: ada 342 Perda Diskriminatif di Indonesia." voaindonesia.com. diakses 25 April 2016, http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-ada-342-perdadiskriminatif-di-indonesia/1736465.html 212 213 GERAKAN MASYARAKAT LOKAL MENGELOLA REMITAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN Dr. Indraddin, S.Sos, M.Si, Jurusan Siologi FISIP Universitas Andalas E-Mail: [email protected] Abstrak Ketika Masalah kemiskinan masih belum teratasi pada masyarakat, akan berdampak negatif terhadap aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, politik, lingkungan, keamanan dan kenyamanan hidup. Pengiriman remitan oleh para migran dari tempat bekerja yang cukup tinggi, sangat membantu program, tentu saja apabila remitan dikelola dengan baik tidak hanya untuk keperluan konsumtif tetapi lebih pada keperluan produktif. Penelitian ini difokuskan melihat gerakan serta upaya masyarakat lokal dalam mengelola remitan dalam rangka mememerangi kemiskinan di kampungnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai panduan diteropong dari sudut pandang teori strukturasi dari Anthony Giddens, didukung dengan konsep-konsep pemberdayaan. Mengambil kasus remitan asal perantau Sumatera Barat, ditemukan bahwa selama ini keterlibatan keluarga luas dan institusi lokal lebih kepada sekedar mengetahui. Uang yang diberikan dikelola secara terpisah, tergantung distribusi oleh para migran, keluarga inti seperti istri, anak, suami atau keluarga luas seperti adik, kakak, mamak dan sebagainya. Remitan migran internasional dan migran domestik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena berkaitan erat dengan ikatan keluarga perantau di nagari masingmasing. Perlu dilakukan gerakan masyarakat lokal, dalam hal ini dipeloporai oleh institusi lokal nagari dengan belajar dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di nagari selama ini. Koordinasi program berbasis Jorong, dan nagari hanya sebagai fasilitor atau mengkoordinir pada tingkat nagari. Kata Kunci: Migran Internasional, Remitan, Institusi Lokal, Pemberdayaan, Pemanfaatan. LOCAL COMMUNITIES MOVEMENT IN MANAGGING OF REMITTENCES FOR POVERTY ALLEVIATION Abstract When the problem of poverty is still not resolved in the community, will have a negative impact on other aspects of life, such as education, politics, the environment, safety and comfort of living. Delivery remittances by migrants from the work place that is quite high, very helpful program, of course, if it si managed properly remittances not only for consumptive purposes but more on productive purposes. This study focused view the movement as well as the efforts of local communities to manage remittances in order alleviate poverty in the village. The study was conducted with a qualitative approach. As a guide in structuration theory of Anthony Giddens struct, supported by the concepts of empowerment. Taking the case of delivery of remittances West Sumatra, it was found that during this extensive family involvement and local institutions is more to just knowing. Money given administered separately, depending on the distribution of migrants, the nuclear family as the wife, children, husbands or extended families such as brother, sister, mamak and so forth. International migrant remittances and domestic migrant can not be separated from one another, as closely associated with family ties in each the village. Need 214 to do the movement of local communities, in this case sponsored by local institutions village by learning from poverty alleviation programs before. Coordination of program based Jorong, and Nagari only as facilitators or coordinated at the level of Nagari. Keywords : International Migrants , Remittances , Local Institutions , Empowerment , Utilization 1. PENDAHULUAN Tidak ada pihak yang tidak sepakat untuk mengentaskan kemiskinan dari muka bumi, karena masalah ini tidak berdiri sendiri, berdampak terhadap lambatnya peningkatan program di sektor lainnya. Menyelesaikan masalah kemiskinan berarti sejalan dengan menyelesaikan masalah di berbagai sektor, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat lebih besar dalam berbagai bidang pembengunan. Untuk itu perlu dilakukan gerakan pengentasan kemiskinan oleh berbagai pihak dengan menggali berbagai potensi yang dimiliki. Menyerahkan permasalahan kemiskinan semuanya kepada pemerintah tidak mungkin, karena terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi persoalan yang sudah begitu pelik di bumi pertiwi. Hasil penelitian berikut adalah merupakan gerakan yang dapat dilakukan oleh institusi lokal nagari dalam memanfaatkan potensi perantau berupa remitan (remittance). Migrasi adalah fenomena umum terjadi di seluruh dunia, hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik di daerah asal maupun di daerah tujuan bermigrasi. Latar belakang perbedaan kondisi sosial ekonomi yang mendorong pergerakan orang dari daerah asal ke tujuan migrasi. Sekitar tiga persen penduduk dunia telah bermigrasi dari negara asal ke negara tujuan untuk bekerja. Pertumbuhan migrasi ini sejak tahun 1990-an telah memberikan kontribusi remitan yang cukup besar bagi negara asal mereka (The World Bank, 2005). Masyarakat Sumatera Barat atau yang dikenal dengan masyarakat Minangkabau, menganut falsafah hidup yang mendorong masyarakatnya untuk bermigrasi. Sebagai mana pepatah adat “karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun” (karatau madang di hulu, berbuah berbunga belum, merantau di saat muda, karena di kampung juga belum berfungsi). Pepatah yang mendorong orang lakilaki untuk pergi merantau yang tujuannya untuk mengadu nasib, memperbaiki ekonomi rumah tangga yang awalnya dilakukan laki-laki, akhirnya juga mengikut sertakan perempuan. Hal itu disebabkan kecendrungan laki-laki yang pergi merantau mencari istri di kampung halamannya sendiri dan akhirnya juga memboyong istrinya pergi merantau. Kebiasaan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang, bahkan saat ini kebiasaan merantau itu tidak saja dimiliki oleh laki-laki muda, tapi juga oleh perempuan seiring dengan perkembangan emansipasi wanita di Indonesia. Migrasi atau dikenal dengan merantau dilakukan dalam rangka merubah nasib (ekonomi keluarga) termasuk keluarga luas. Secara umum migrasi internasional sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya yang masih tinggi, sangat tidak mungkin aktivitas perekonomian negara tersebut dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Maka di zaman orde baru, terus berlangsung sampai sekarang, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dipandang sebagai salah satu strategi pemecahan masalah ketenagakerjaan setiap orde pemerintahan di Indonesia. Dalam teori ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, hal ini sering dinyatakan sebagai “the first stage of labor migration transition” (Tjiptoheriyanto, 1997). 215 Proses migrasi baik nasional maupun internasional berdampak positif bagi negara tujuan, negara asal dan para migran berserta keluarganya. Bagi negara tujuan, kehadiran migran ini dapat mengisi segmen-segmen lapangan kerja yang sudah ditinggalkan oleh penduduk setempat karena tingkat kemakmuran negara tersebut semakin meningkat. Lapangan kerja tersebut seperti sektor perkebunan dan bangunan atau konstruksi yang banyak digantikan oleh pekerja-pekerja dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ini terlihat di negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Sementara kebutuhan tenagatenaga terampil yang jumlahnya kurang, seperti sebagai tenaga kerja teknisi dan jasa biasanya dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah, negara tetangga seperti Singapura, Brunai. Bagi negara asal merupakan sumber penerimaan devisa dari remittances hasil kerja migran di luar negeri. Sementara untuk para migran, kesempatan ini merupakan pengalaman internasional dan kesempatan meningkatkan keahlian, juga akan mengenal disiplin kerja di lingkungan yang berbeda. Bagi keluarga migran hal tersebut merupakan sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Haris, 2007). Pada mulanya istilah remitan (remittance) adalah uang atau barang yang di kirim oleh migran ke daerah asal, sementara migran masih berada di tempat tujuan (Connell, 1976). Namun kemudian definisi ini mengalami perluasan, tidak hanya uang dan barang, tetapi keterampilan dan ide juga digolongkan sebagai remitan bagi daerah asal (Connell, 1980), keterampilan yang diperoleh dari pegalaman bermigrasi akan sangat bermanfaat bagi migran jika nanti kembali ke daerahnya. Ide-ide baru juga sangat menyumbang terhadap pembangunan desanya. Misalnya cara-cara bekerja, membangun rumah dan lingkungannya yang baik, serta hidup sehat. Pengertian remitan secara umum berasal dari transfer, baik dalam bentuk cash atau sejenisnya, dari seorang asing kepada sanak keluarga di negara asalnya. IMF mendefiniskannya ke dalam 3 kategori yaitu (1) remitan pekerja atau transfer dalam bentuk cash atau sejenisnya dari pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman. (2). Kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau renumerasi dalam bentuk cash atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang bekerja di satu negara lain di mana keberatan mereka adalah resmi, dan (3). Transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer kapital dari aset keuangan yang dibuat orang asing tersebut sebagai perpindahan dari satu negara ke lainnya dan tinggal lebih dari satu tahun. Menurut Wikipedia, remitan (remittance) adalah transfer uang oleh pekerja asing ke negara ke tempat mereka berasal. Pada hakekatnya masuknya uang tunai dalam jumlah relatif besar di dalam sistem perekonomian rakyat atau perdesaaan merupakan fenomena yang relatif dapat dipertimbangkan bagi kemajuan faktor ekonomi perdesaan itu sendiri. Perekonomian perdesaan yang didominasi oleh usaha tani kecil, pedagang kecil tidak memungkinkan petani dan pedagang untuk menghasilkan serta menghimpun modal usaha. Sistem tanam paksa, sistem ekonomi liberal yang diterapkan serta masa berlangsungnya involusi pertanian mengakibatkan penduduk pedesaan kehilangan peluang mengumpulkan modal. Masuknya devisa bermilyar dolar ke dalam sistem ekonomi perdesaan pada beberapa dekade terakhir ini merupakan potensi yang tidak kecil artinya terhadap ekonomi pedesaan. Remitan atau transfer uang oleh pekerja asing ke negara dan tempat mereka berasal dari para pekerja asing ke luar negeri telah membantu memperkuat keseimbangan pembayaran dan anggota keluarga pekerja yang kebanyakan adalah dari daerah pedesaan dan wilayah pertanian berada dalam garis kemiskinan. Oleh sebab pemerintah Indonesia menganut sistem devisa terbuka, maka besarnya remitan yang dikirim oleh buruh migran dari luar negeri tidak dapat terlacak dengan baik. Kebanyakan data mengenai remitan bertumpu pada laporan dari institusi formal saja, sementara pada kenyataannya saluransaluran informal pengiriman serta uang yang dibawa sendiri oleh buruh migran sewaktu 216 mereka pulang ke kampung menjadi sesuatu yang umum, maka banyak pihak yang berpendapat bahwa remitan yang tercatat paling banyak hanya setengah dari kenyataannya. Penelitian tentang migrasi internasional sudah banyak dilakukan, namun suatu kajian integratif yang menunjukkan bagaimana remitan dikirim dan dimanfaatkan didaerah asal masih belum dikaji secara khusus, bagaimana remitan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga migran di daerah asal. Menarik untuk dikaji dari perspektif lain yaitu melalui pemberdauyaan intitusi lokal. Penelitian Indraddin (2011) menemukan bahwa remitan menjadi pendukung program pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal, kerena perantau merupakan potensi pendukung program pemberdayaan institusi lokal dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menarik dan penting artinya karena pengentasan kemiskinan perlu terus diupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanah Undang Undang Dasar. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa pengentasan kemiskinan lebih tepat menggunakan pendekatan pemberdayaan institusi lokal guna menjamin keberlanjutan program. Salah satu faktor pendukung adalah kekuatan perantau suatu daerah. Pengetahuan tentang aliran dana dan bagaimana penggunaan uang tersebut digunakan, oleh siapa uang tersebut dikelola, berapa besar uang tersebut, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan investasi, kemana uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif dan investasi; serta bagaimana pengaruh masuknya uang terhadap kegiatan perekonomian rakyat, kelembagaan ekonomi sosial, nilai masyarakat serta kehidupan keluarga masih relatif belum begitu menjelaskan bagaimana yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Pengetahuan ini diperlukan untuk berbagai kepentingan, untuk merancang bagaimana pola pembinaan penggunaan remitan setelah pekerja migran itu memperoleh remitan di daerah tujuan di luar negeri dan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehingga kesejahteraan bisa meningkat. Tulisan ini didasarkan kepada temuan penelitian tahun II, dimana temuan penelitian tahun pertama juga telah diseminarkan pada forum Seminar Nasional Peran Ilmu Ilmu Sosial Dalam Pemerintahan Indonesia Baru bulan Oktober 2014 lalu. Pada tahun ke II ini tujuan penelitian menemukan model pemberdayaan institusi lokal dalam pemanfaatan remitan. 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsepsi Remitan Secara teoritis keberlanjutan program dalam pemberdayaan salah satunya dengan pemberdayaan institusi lokal. Institusi lokal berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang masih berlaku dalam masyarakat, termasuk kelembagaan adat yang masih didukung keberadaaanya oleh masyarakat. Suatu kebudayaan akan berlangsung bila ada tiga faktor, yaitu adanya nilai-nilai yang berkembang, adanya pelopor pada budaya tersebut, dan adanya pendukung. Hasil penelitian Indraddin (2011), tentang pengentasan kemiskinan berbasis nagari menunjukkan bahwa untuk menjamin keberlajutan program pemberdayaan masyarakat miskin perlu melibatkan insitusi lokal nagari. Institusi lokal yang dipakai sesuai karakteristik nagari masing-masing, karena berbeda nagari, berbeda juga institusi lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Institusi lokal nagari perlu didukung oleh elemen lain, seperti orang kaya yang ada di kampung itu termasuk dana yang berasal dari perantau. Perantau dalam tulisan ini terdiri dari dua bentuk, pertama di dalam negeri, kedua di luar negeri atau migrant internasional. Pada mulanya istilah remitan (remittance) adalah uang atau barang yang dikirim oleh migran ke daerah asal, sementara migran masih berada ditempat tujuan (Connell, 1976). Namun kemudian definisi ini mengalami perluasan, tidak hanya uang dan barang, tetapi ketrampilan dan ide juga digolongkan sebagai remitan bagi daerah asal, ketrampilan 217 dan ide inilah yang dapat juga menjadi dasar kreatifitas mantan migran dalam memberdayakan keluarga mereka di daerah asal sekembalinya dari merantau. Ketrampilan yang diperoleh dari pengalaman bermigrasi akan sangat bermanfaat bagi migran jika nanti kembali ke desanya ide-ide baru juga sangat menyumbang pembangunan desanya. Misalnya cara-cara bekerja, membangun rumah dan lingkungannya yang baik, serta hidup sehat dan lain sebagainya. Remitan menurut Curson (1981) merupakan pengiriman uang, barang, ide-ide pembangunan dari daerah tujuan migrasi ke daerah asal dan merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dari segi ekonomi keberadaan remitan sangatlah penting karena mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan juga untuk kemajuan bagi masyarakat penerimanya. Pengiriman remitan bagi perantau yang berasal dari masyarakat perdesaan kepada kerabatnya merupakan kesatuan ekonomi. Remitan atau yang lazim mereka sebut “kiriman” selain ditujukan untuk keluarganya juga ditujukan untuk anggota masyarakat desanya dan juga untuk keperluan desa asalnya. Remitan atau kiriman yang ditujukan untuk keluarganya lebih bersifat ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, untuk biaya pendidikan, kesehatan dan untuk menunjang kehidupan orang tua “penganti” seperti simbah-simbah (nenek dan kakek, keluarganya) yang menggantikan peran orang tua. Selain dalam bentuk uang para masyarakat migran juga mengirim barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat elektronik, dan juga mampu menginvestasikan kiriman dengan membeli tanah serta membuka usaha baru di desanya yang dijalankan oleh anggota keluarganya yang masih tinggal di desa. Remitan dalam konteks migrasi di negara-negara sedang berkembang merupakan upaya migran dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial ekonomi dengan daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. Selain migran mengirim remitan karena secara moral maupun sosial mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan (Curson, 1983). Kewajiban dan tanggung jawab sebagai migran, sudah ditanamkan sejak masih kanak-kanak. Masyarakat akan menghargai migran secara rutin mengirim remitan ke daerah asal dan sebaliknya akan merendahkan migran yang tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam perspektif yang lebih luas, remitan dari migran dipandang sebagai suatu instrumen dalam memperbaiki keseimbangan pembayaran, dan merangsang tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa remitan menjadi komponen penting dalam mengkaitkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan di daerah Jatinom Jawa Tengah (Effendi, 1993). Sejak pertengahan tahun 1980 an seiring dengan meningkatnya mobilitas pekerja, terjadi perubahan pola makanan keluarga migran di daerah asal menuju pola makanan dengan gizi sehat. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari peningkatan daya beli keluarga migran di daerah asal, sebagai akibat adanya remitan. Namun disisi lain, remitan ternyata tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi keluarga migran di daerah asal. Dalam kerangka pempupukkan remitan, migran berusaha melakukan berbagai kompromi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, dan mengadopsi pola konsumsi tersendiri di daerah tujuan. Para migran akan melakukan “pengorbanan” dalam hal makanan, pakaian, dan perumahan supaya bisa menabung dan akhirnya bisa mengirim remitan ke daerah asal. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa besarnya remitan yang dikirimkan migran ke daerah asal relatif bervariasi. Penelitian yang dilakukan Rose dan kawan-kawan (1969) dalam Curson 1983 terhadap migran di Birmingham menemukan bahwa remitan migran India sebesar 6,3 persen dari penghasilannya sedangkan migran Pakistan mencapai 12,1 persen. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan Jellinek (1978) 218 dalam Effendi (1993) menemukan bahwa remitan yang dikirimkan para migran penjual es krim di Jakarta mencapai 50 persen dari penghasilan yang diperolehnya. Besar kecilnya remitan ditentukan oleh berbagai karakteristik migrasi maupun migran itu sendiri. Rempel dan Lobdell (1978) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan migran, maka akan semakin besar remitan yang dikirimkan ke daerah asal. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan fungsi remitan sebagai pembayaran kembali (repayment) investasi pendidikan yang telah ditanamkan keluarga kepada individu migran. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan migran menunjukkan besar kecilnya investasi pendidikan yang ditanamkan keluarga, dan pada tahap selanjutnya berdampak pada besar kecilnya repayment yang diwujudkan dalam remitan. Pengaruh positif juga ditemukan antara penghasilan migran dan remitan (Wiyono, 1994). Remitan pada dasarnya adalah bagian dari penghasilan atas dua bagian besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, serta keluarga di luar keluarga inti. Dalam konteks ini, Mantra (1994) mengemukakan bahwa remitan akan lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah keluarga inti. Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di daerah asal bukan keluarga inti. Tujuan pengiriman remitan akan menentukan dampak remitan terhadap pembangunan di daerah asal. Berbagai pemikiran dari hasil penelitian telah menemukan keberagaman tujuan remitan ini, namun demikian dapat dikelompokkan atas tujuan-tujuan sebagai berikut: Bentuk investasi adalah perbaikan dan pembangunan perumahan, membeli tanah, mendirikan industri kecil dan lain-lainnya. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam menjaga kelangsungan hidup di daerah asal, tetapi juga bersifat psikologis, karena erat hubungannya dengan prestise seseorang. Effendi (1993) dalam penelitiannya di tiga desa di Jatinom, Klaten menemukan bahwa remitan telah digunakan untuk modal usaha pada usaha-usaha skala kecil seperti pertanian jeruk, peternakan ayam, perdagagan dan bengkel sepeda. Namun banyak juga pemanfaatan uang tidak fungsional karena ketidak mampuan mereka memanfaatkan secara baik. Mereka juga banyak menymbang untuk pembangunan desa mereka, namun hal itu belum dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Migran mempunyai keinginan, jika mereka mempunyai cukup uang ada sudah pensiun, mereka akan kembali ke daerah asal. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi investasi, mereka akan membangun rumah atau membeli tanah di daerah asal sebagai simbol kesejahteraan, prestisius dan kesuksesan di daerah rantau. Lee (1992) mengemukakan bahwa berbagai pengalaman baru yang diperoleh di tempat tujuan, apakah itu keterampilan khusus atau kekayaan, sering dapat menyebabkan orang kembali ke tempat asal dengan posisi yang lebih menguntungkan selain itu tidak semua yang bermigrasi bermaksud menetap selama-lamanya di tempat tujuan. Dalam penelitian ini pengertian remitan yang akan digunakan mengacu kepada remitan dalam bentuk uang yang dihasilkan oleh buruh migran selama bekerja di luar negeri, baik yang dikirim maupun yang dibawa langsung oleh buruh migran ke kampung halamannya. Remitan termasuk uang yang dikirim oleh organisasi perantau yang ada di luar negeri, karena selama ini perantau lewat lembaga yang ada juga mengirim uang untuk pembangunan kampung halamannya. Penggunaaan remitan dipengaruhi oleh banyak variabel. Dari sisi si buruh migran faktor yang mempengaruhi adalah tingkat penghasilan, lama bekerja di luar negeri dan sebagainya. Dari sisi rumah tangga di daerah asal, cenderung menggunakan remitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (makanan, pakaian, kesehatan) dan untuk membangun atau renovasi rumah, membeli tanah atau ternak atau barang-barang lainnya. Ada yang memandang bahwa pengeluaran ini adalah bukan “investasi produktif” misalnya 219 kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan dan mempekerjakan orang, atau usaha atau aktivitas lainnya yang memiliki multiplier effect. Pandangan alternatif melihat bahwa penggunaan remitan tersebut adalah rasional, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan struktural untuk berinvestasi (Primawati, 2008). Puri dan Ritzema (1999: 15) menyimpulkan bahwa keluarga buruh migran menggunakan remitannya secara rasional. 1. Pemberdayaan Masyarakat Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya. Pemberdayaan pada dasarnya sebuah proses pelibatan masyarakat lokal sejak awal pelaksanaan program, dan proses tersebut menumbuhkan rasa memiliki kepada masyarakat. Pemberdayaan (empowering) suatu upaya menjadikan orang, kelompok dari powerless menjadi empower. Terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), proyek peningkatan masyarakat pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Paling tidak, ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND) sejak tahun 2004. Pemberdayaan dicirikan dengan menumbuhkan keberdayaan suatu masyarakat. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, meraka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah ekonomi dan lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal. Kemandirian dapat dilihat dari kemandirian individu dan kemandirian kelompok. Kelompok juga akan maju jika ada orang menjadi pelopor atau penggerak di komunitasnya. Jadi peranan individu bisa saja dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan komunitasnya. Kemandirian diukur sejauh mana individu atau kelompok dapat mengurus diri sendiri bila program atau pendapingan program berakhir. Pemberdayaan memerlukan keseriusan bagi pelakunya. Tantangan proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat dalam proyek bersangkutan. Menurut Tilden: dalam Arifin (2003), mengenai keterampilan dan sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) kegiatan penting yakni: Problem solving (pemecahan masalah); Sense of Community (peduli terhadap masyarakat); Sense of mission (komitmen terhadap misi proyek); dan Honesty with self and with others (jujur kepada diri sendiri dan orang lain). Menurut Rahayu (2006), dalam bukunya “Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Jamasy ( 2004), menyatakan bahwa para pelaku program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program. Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal pelaku pemberdaya. Pertama, para pelaku utama pemberdaya 220 dan seluruh unsur stakeholders, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya dua hal diantaranya akan menjadi sangat penting yakni: Keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Twelvetrees (1991), membagi perspektif teoritik pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan professional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neoMarxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab kelemahan mereka, serta analisis sumbersumber ketertindasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Payne sebagai sebuah model pendekatan dengan dukungan minoritas masyarakat, sebagai contoh penggambaran perhatian terhadap keseimbangan ketetapan pelayanan. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformatif. 3.METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Untuk mendapatkan perspektif pengkajian remitan dan model pemberdayaan keluarga migran penelitian ini menerapkan startegi sebagai berikut: keluarga mantan migran asal Sumatera Barat sebagai unit analisisnya diidentifikasi menurut lokasi tempat bekerja. Kemudian iformasi dari keluarga dikonfirmasi kepada keluarga luas dan tokoh masyarakat. Triangulasi data memang sangat mungkin dilakukan mengingat keluarga luas masih berjalan di lokasi penelitian. Untuk akurasi dan kedalaman data, digunakan teknik diskusi terfokus (FGD) di tingkat nagari. Pada saat pelaksanaan FGD muncul berbagai informasi, karena peserta umumnya mengetahui situasi sosial yang diterliti. Teknik menentukan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kombinasi teknik purposive dengan snowballing, dimana sejak awak peneliti telah menentukan kriteria informan bahkan lokasinya sejak awal sesuai kriteria penelitian ini. Kriteria lokasi ditentukan dari informasi awal terdapatnya migran Internasional asal Sumatera Barat. Maka kabupaten yang dipilih adalah Kabupatren Lima Puluh Kota dan Solok. Dari dua kabupaten itu dipilih Nagari Suayan dan Sulit Air sebagai lokasi penelitian. Sedangkan informan yang dipilih adalah Kerabat migran, keluarga luas, tokoh masyarakat nagari yang terdiri dari lima unsur yang ada di nagari. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan nagari dan Nagari Sulit Air di Kabupaten Solok. Lokasi penelitian tahun pertama, sama dengan lokasi tahun kedua, karena penelitian ini berkaitan antara tahun pertma dengan tahun kedua. Pada awalnya penentuan lokasi penelitian didasarkan pada 221 informasi umum tentang keberadaan perantau asal Minangkabau di luar negeri, maka direncanakan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Namun saat dilakukan penelitin awal untuk menentukan nagari yang akan dijadikan lokasi penelitian, ternyata di kabupaten Tanah Datar perantau luar negerinya sedikit sekali, tidak terdapat jumlah yang dapat memperlihatkan pola interaksi yang memadai dengan kerabat di tempat asal. Informasi awal menunjukkan bahwa di Tanah Datar nagari yang memiliki perantau luar negeri adalah nagari Batipuah Baruah, dan beberapa Nagari di Kecamatan Lintau. Peneliti menelusuri nagari tersebut, dan kenyataannya memang tidak banyak jumlah masyarakatnya yang merantau ke luar negeri. Akhirnya lokasi yang di Tanah Datar diganti dengan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Solok, yaitu nagari Sulit Air. Nagari Sulit Air ternyata perantaunya ada di Malaysia, Singapura, Brunai, Australia, dan Amerika. Pada tahun pertama penelitian lebih terfokus pada migran internasional, sementara pada tahun kedua migran nasional (domestik) menjadi kajian juga dalam penelitian, karena berdasarkan temuan penelitian tahun pertama, bahwa antara migran internasional dan domestik tidak dapat dipisahkan, karena mereka berada dalam satu garis koordinasi pada ikatan perantau nagari tersebut. Nagari Suayan Suayan adalah salah nagari di kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 70-an masih dikategorikan nagari tertinggal. Saat itu pendidikan masyarakatnya masih tertinggal dinggal dibandingkan nagari sekitarnya, sehingga melekat lebel yang berkonotasi negatif terhadap masyarakat Suayan saat itu bila disebut nagari Suayan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ketika gelombang merantau ke Malaysia dimulai tahun 1980-an, performen nagari Suayan menjadi berubah. Seiring meningkatnya ekonomi masyarakat terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga yang merantau ke luar negeri (umumnya Malaysia), tingkat ekonomi mulai meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan masyarakat. Sejarah merantau ke Malaysia jangan dibayangkan sebuah perjalanan ke luar negeri dengan prosedur administrasi sebagaimana aturan memasuki suatu negara yaitu dengan kelengkapan administrasi seperti kartu identitas (pasport) dan izin memasuki suatu negara berupa visa dan exeet permit, namun suatu perjalanan illegal (menyelundup lewat Kepulauan Riau). Perjalanan illegal ersebut akhirnya menjadi perjalanan yang mengikuti prosedur administrasi suatu negara sampai saat ini. Informasi dari tokoh masyarakat dan orang yang pernah merantau ke Malaysia menyatakan bahwa, perjalanan illegal dilakukan saat itu salah satunya disebabkan ketidak kenalan mereka terhadap administrasi kependudukan terutama berurusan dengan imigrasi. Dulu menurut mereka, kantor imigrasi itu adalah suatu lokasi administrasi yang jauh dan sulit diakses. Maka perjalanan secara illegal menjadi pilihan perjalanan yang dilakukan. Selain itu sanksi yang diterapkan bagi yang ketahuan melanggar juga belum seberat yang diberlakukan sekarang ini. Nagari Sulit Air Nagari Sulit Air merupakan salah salah satu nagari di Kabupaten Solok yang berada di wilayah administrasi kecamatan X Koto Diatas yang bisa diakses melalui Kota Solok atau dari pinggir Danau Singkarak. Dari Kota Solok melalui Kampung Jawa, terus ke Nagari Aripan, Nagari Paninjauan, lalu akan bertemu dengan Nagari Sulit Air. Atau dapat juga diakses dari pinggir danai singkarak, yaitu melalui nagari Singkarak atau bisa juga dari Ombilin. Jarak nagari Sulit Air dari pinggir danau singkarak kira-kira 30 km, sedangkan dari Kota Solok jaraknya hampir sama dengan ke pinggir danau singkarak. Walau letaknya jauh di perbukitan, namun dengan kondisi jalan yang cukup bagus ke 222 daerah ini, maka dapat ditempuh dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Mendengar nama Sulit Air saat ini terbayang dalam fikiran orang Sumatera Barat sebuah nagari dimana masyarakatnya adalah perantau yang sukses. Saat lebaran tiba, para perantau pulang bersama, atau yang dikenal oleh orang minang “pulang basamo”. Saat itu terlihat pertambahan penduduk Sulit Air dengan berjubelnya kendaraan pribadi dengan berbagai merek dan model yang berdatangan dari berbagai kota besar di Indonesia. Berbeda halnya dengan zaman dulunya, menurut tokoh masyarakat Sulit Air bahwa konotasi negatif melekat pada nagari ini, seperti dalam profil Sulit Air di bawah ini : “Suli Aie ” Orang Minang melafalkan dua kata di atas. Kata-kata pedas itu merupakan nama sebuah Nagari yang tersuruk di perbukitan Danau Singkarak Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mendengar namanya saja, bulu kuduk segera berdiri. Membayangkan sebuah perkampungan kumuh di perbukitan batu cadas yang tandus dengan sawah-sawah dikotori rumput-rumput liar yang juga tak sanggup hidup lagi. Masyarakat penghuninya tinggal di gubug-gubug reot berlantai tanah. Perkampungan hanya dihuni laki-laki tua dan wanita renta serta anak-anak caludih berkulit legam terpanggang matahari. Anak-anak kecil bermain dalam simbahan debu tanpa alas, mereka yang lebih besar membawa tempayan di kepala menuruni perbukitan terjal menuju sumber air, Danau Singkarak. Penampilan Sulit Air dulu dengan sekarang ternyata berbeda, tidak ada lagi kelangkaan air sekalipun kemarau melanda teramat panjang. Sawah dan ladang dapat menghasilkan padi serta tanaman khas seperti kulit manis (sebutan untuk kayu manis), dan tanaman kebun lainnya. Sulit Air bukanlah tanah yang gersang seperti namanya melainkan perbukitan yang subur makmur. Pembangunannya melebihi nagari-nagari lain di Sumatera Barat. Berbaliknya rupa wajah dengan nama yang melekat sampai sekarang itu ternyata tidak lepas dari peran perantau asal Nagari Sulit Air yang tersebar di seantero tanah air dan juga luar negeri. Jumlah remitan yang dikirim oleh para migran dari tempat bekerja cukup tinggi, kondisi ini sangat membantu mengentaskan kemiskinan para migran apabila remitan dikelola dengan baik tidak hanya untuk keperluan konsumtif tetapi lebih pada keperluan produktif. Pada penelitian tahun pertama ditemukan bahwa, proses pengiriman remitan oleh migran internasional asal Sumatera Barat dalam dua bentuk, pertama dikirim melaluim teman sesama perantau, hal ini dilakukan timbal balik, karena mereka saling berkirim bagi siapa yang pulang kampung pada waktu tertentu. Kedua lewat bank, hal ini dilakukan kepada bank yang mudah diakses oleh keluarga di kampung. Proses yang beragam ini menyebabkan sulitnya mendapatkan data pasti berapa jumlah remitan yang dikirim perantau ke kampung halamannya. Keterlibatan institusi lokal dalam proses pengiriman tersebut dapat dibedakan atas kiriman keluarga dan kiriman untuk pembangunan. Di tingkat keluarga pihak yang terlibat adalah keluarga inti samapai keluarga luas, namun keluarga luas seperti mamak kaum hanya mengetahui, tidak terlibat dalam pengelolaan penggunaan uang tersebut. Di tingkat institusi keterlibatan tokoh masyarakat formal dan informal pada kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman, baik bangunan fisik maupun melaksanakan sebuah kegiatan. Ikatan emosional perantau adaa pada level jorong, bukan nagari, maka pengelolaan remitan untuk pembangunan seyogyanya dilakukan di tingkat jorong. Maka penelitian tahun II dilakukan untuk menyusun model berdasarkan masukan dan rangcangan pada tahun I. 2. Proses dan Pola Pengiriman Remitan 223 Sebagaimana temuan penelitian tahun pertama tentang proses pengiriman uang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua, pertama dikirim melalui teman, dimana para perantau mengirimkan uang untuk keluarga mereka kepada saudara atau teman yang pulang kampung. Kepada orang yang pulang kampung ini telah diberikan pesan kepada siapa saja uang itu akan diberikan. Perantau yang mengirim biasanya telah mengorder kepada siapa saja uang akan diberikan, misalnya kepada bapak, ibu, anak atau saudara lainnya. Merantau ke negeri orang ternyata tidak mengurangi hubungan kekerabatan yang ada pada mereka, malah kekerabatan berkembang dari pertemanan menjadi karib kerabat baru. Semula di kampung belum saling mengenal, karena tinggal di nagari tetangga, misalnya bagi orang Suayan nagari tetangga adalah Batu Hampa, yang semula di kampung belum kenal, karena merantau menjadi kenal dan akhirnya berkembang menjadi kerabat baru. Mereka saling menjalin hubungan baik layaknya seperti keluarga luas semasa di kampung. Kedua, melalui bank, biasanya dikirim langsung kepada rekening orang atau keluarga yang dituju. Saat ini bank bukanlah suatu yang aneh, masyarakat perdesaan telah menggunakan bank sebagai media menyimpan uang dan peminjaman. Di lokasi penelitian ditemukan penggunaan jasa bank adalah salah satu dampak dari tingginya jumlah perantau di nagari tersebut. Suayan dengan kondisi georgafis dimana infrastrukturnya cukup baik, memudahkan masyarakat mengakses bank ke Kota Payakumbuh. Menurut keluarga migran, tidak sulit bagi mereka untuk pergi ke bank mengambil uang jika ada kiriman dari saudara mereka di luar negeri. Di nagari Sulit Air terdapat sedikit perbedaan pada proses pengiriman dibandingkan dengan perantau yang berasal dari Suayan. Walaupun sama menggunakan jasa bank, perantau di Australia, mengirim uang ke kampung lewat rekening saudaranya di Jakarta. Saudara di Jakarta yang membawa uang yang sudah diamplopkan ke kampung (Sulit Air). Dengan banyaknya perantau luar negeri, bank BRI unit yang biasanya di Sumatera Barat terdapat di ibu kecamatan, namun di Sulit Air Bank BRI hadir di ibu Nagari Sulit Air. Dengan adanya fasilitas bank ini, sangat memudahkan masyarakat mengambil uang kiriman dari saudara dirantau. Pada tahun kedua penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kaiatan yang erat antara remitan migran internasional dengan remitan yang berasal dari perantau domestik. Hal ini terkait dengan ikatan perantau asal nagari tersebut. Ikatan perantau nagari sulit air misalnya, keberadaan organisasi Sulit Air Sepakat (SAS), tidak terlepas dari dukungan perantau yang yang ada di luar negeri dan dalam negeri juga. Pengiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung terkoordinasi dan menyatu dalam organisasi tingkat pusat yang selanjutnya dikirim ke kampung halaman. Orang yang diharapkan turun langsung menyampaikan bantuan biasanya pengurus pusat yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan “pulang basamo” yang mereka jadwalkan sekali dalam dua tahun, terkoordinir antara perantau luar negeri dan perantau domestik. Dari proses pengiriman, temuan penting adalah bahwa terdapat dua janis pengiriman yang dilakukan oleh perantau ke kampung halaman, pertama kiriman yang ditujukan untuk keluarga, kedua kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman. Kiriman untuk kampung halaman ini belum terkelola dengan baik, baik oleh organisasi perantau itu sendiri, maupun oleh institusi lokal yang ada di kampung. Perlu dilakukan pemberdayaan atas kelembagaan yang potensial mengelola remitan. Model pemberdayaan ini masih disempurnakan saat tulisan ini dibuat. 1. Peran Institusi Lokal Keterlibatan institusi lokal nagari dalam pemanfaatan remitan selama ini memiliki dinamika yang cukup panjang. Beda nagari, berbeda pengalaman yang mereka alami, namun remitan diakui sebagai salah satu penopang dana pembangunan nagari (desa) 224 selama ini. Menurut tokoh masyarakat Suayan, terjadi krisis kepercayaan perantau terhadap lembaga yang ada di kampung, hal ini disebabkan beberapa pengalaman masa lalu, dimana kiriman yang diberikan perantau kepada kampung halaman tidak mencapai sasaran. Namun disisi lain di nagari Sulit Air pengakuan masyarakat dan pemerintah nagari bahwa keberhasilan pembangunan di nagari tidak terlepas dari dukungan dana dari perantau. Tidak saja berupa dana, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan pemikiran dan jaringan dengan pihak luar. Berdirinya cabang pesantren Gontor di Sulit Air tidak terlepas dari jaringan yang dibangun oleh perantau terhadap masyarakat nagari Sulit Air. Informasi tersebut dibenarkan oleh perangkat pemerinntah nagari, dimana perantau saat mengirim bantuan kepada nagari diiringi oleh rasa keterikatan terhadap kerabat terdekat. Misalnya diberikan bantuan terhadap keluarga miskin yang ada di kampung. Keterlibatan institusi lokal dapat diklasifikasikan kepada dua, pertama kiriman untuk keluarga, melibatkan institusi paruik (suku), unsur yang terlibat di dalammua adalah mamak kepala waris.au yang dikenal dengan tungganai. Tapi bisa saja makam tersebut adalah ninik mamak (penghulu) dalam suku tersebut. Pada tataran paruik biasanya diketahui oleh keluarga inti, bapak, ibu nenek, paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu atau yang disebut mamak kaum. Mamak biasanya diberi khabar, namun tidak diberitahu jumlah uang yang dikirim. Mamak hanya mengetahui jumlah uang jika diberikan tersendiri lewat kiriman oleh anak kemenakannya. Pengakuan beberapa mamak kaum di Sulit Air dan di Suayan, bahwa mereka mengetahui kalau ada kiriman uang dari rantau, tapi mereka hanya sebatas tahu saja, menurutnya tidak enak rasanya ikut campur lebih jauh. Artinya peran mamak menentukan kebijakan dalam sebuah kaum tidak begitu besar fungsinya dalam mengatur kiriman yang ditujukan ke keluarga oleh perantau. Namun bila kiriman itu untuk membangun rumah, maka mamak akan membantu dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut. Peran yang lebih besar dilakukan mamak dan ninik mamak bila salah seorang perantau sukses ingin membangun rumah gadang (temuan penelitian tahun I). Kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman pada penelitiaan tahun I ditemukan bahwa jumlahnya beragam, namun akumulasinya cukup besar mendukung pembangunan yang ada di nagari tersebut. Bantuan ini biasanya dikirim lewat organisasi persatuan kampung. Biasanya mereka kumpulkan dulu di organisasi perantau di luar negeri, lalu lembaga (ikatan keluarga kampung yang ada di Jakarta) biasanya yang mengirim ke kampung halaman. Biasanya dilakukan dengan mengantar langsung ke kampung halaman, namun ada juga yang mengirimkan lewat ikatan perantau domestik. Potensi kiriman lebih besar di Sulit Air dibanding Suayan, hal ini berhubungan dengan keaktifan organisasi perantau mereka. Sulit Air dengan organisasi perantaunya (SAS) yang cukup profesional, telah berhasil membangun infrastuktur pedesaan seperti jalan, jembatan, dan sarana pendidikan. Lewat SAS dan yayasan pembangunan kampung yang mereka bangun telah berhasi membangun Pesantren cabang Gontor, jalan, jembatan, dan sebagainya. Kiriman tipe kedua ini melibatkan banyak unsur yang ada dalam masyarakat. 2. Jorong sebagai Basis Pemberdayaan Semangat kembali ke nagari yang diterapkan oleh masyarakat Sumatera Barat bukanlah disimpulkan bahwa nagari secara terpusat dijadikan basis pembangunan. Hal ini ditemukan di Suayan maupun Sulit air bahwa basis pemberdayaan masyarakat strategisnya dilaksanakan berbasis jorong. Jorong menjadi basis geografis dan kekerabatan dalam sebuah nagari. Selain terlalu luas, nagari juga punya keberagaman suku di dalamnya, sementara jorong terpusat secara geografis, dan lebih homogen dalam kekerabatan yang berbasis suku. Ikatan emosional masyarakat berada di tingkaat jorong, hal ini terlihat dari keberadaan ikatan kekerabatan masyarakat pada tingkat jorong. Jadi selain acara lembaga 225 tingkat nagari, di rantau justru hidup kelompok di tingkat jorong. Hal itu berimplikasi terhadap proses pengiriman bantuan ke kampung halaman. Bila langsung dikirim ke pemerintah nagari, maka ada kekuatiran jorong mereka tidak akan dapat porsi yang memadai dari uang yang dikirimkan. Kedua nagari mengakui hal tersebut, sehingga banyak juga peraantau yang mengirim langsung bantuan kepada jorongnya masing-masing. Selama ini pemerintah nagari belum berbuat banyak, karena melihat kebiasaan itu berlangsung sudah lama. Namun hasil diskusi terfokus tentang pengelolaan dana remitan pada level nagari menunjukkan bahwa basis jorong dilihat lebih efektif dalam menggaet remitan dari perantau sebagai pendukung pembangunan. Pelibatan Kepala jorong dan ninik mamak kaum bisa sebagai pendukung jalannya koordinasi, namun kelembagaan ninik mamak kaum atau suku belum bisa dijadikan lembaga yang berperan aktif, tapi lebih sebagai dukungan. 3. Model Pemberdayaan Institusi Lokal Konsep institusi lokal dalam penelitian ini merujuk nilai-nilai utama yang masih berlaku dalam masyarakat berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan budaya dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu saja akhirnya berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, karena dalam tatanan masyarakat Minangkabau fungsi keluarga luas salah satunya adalah melindungi keluarganya dari berbagai ancaman yang berpotensi merendahkan martabat keluarga tersebut. Kemiskinan adalah sebuah aib bagi keluarga, saat ada keluarga yang dikatakan “bansaik”, merupakan malu bagi keluarga luas. Ini sesuai dengan nilai adat, “sehino samalu”, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Institusi juga berkaitan dengan kelmbagaan adat, atau kelembagaan yang ada orang di dalamnya, tapi tidak ada struktur yang jelas, seperti ninik mamak, parit paga nagari, bundo kanduang dan sebagainya. Hasil FGD terhadap rangcangan model yang disusun pada tahun pertama penelitian ini terjaring informasi bahwa beberapa asumsi terhadap intitusi lokal tidak lagi berjalan secara ideal, namun telah terjadi beberapa perubahan sesuai perkembangan zaman. Sebelum menyusun model dalam penelitian ini telah ditelusuri nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat di lokasi penelitian, kemudian dianalisis dengan konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa kekuatan yang dapat mendukung model: a. Ikatan Kekerabatan Kampung Organisasi bentukan berupa ikatan keluarga suatu kampung Bagi masyarakat Sumatera Barat tidak asing lagi, hampir semua nagari punya ikatan keluarga perantau. Organisasi bentukan di sini adalah mengacu pada organisasi moderen yang profesional. Organisasi perantau Sulit Air Sepakat (SAS) adalah salah satu contoh kelembagaan bentukan yang cukup ampuh digunakan untuk pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan remitan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Indraddin (2011), bahwa pengentasan kemiskinan berbasis nagari dilakukan dengan pembentukan badan pengentasan kemiskinan di tingkat jorong. Jadi institusi lokal yang digunakan adalah nilai-nilai yang masih dianut masyarakat, sementara lembaga dalam bentuk asosiasi adat sudah jarang yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya, KAN, LPM, BAMUS, Parik Paga Nagari, dan bermacam lembaga yang ada di nagari tidak lagi punya perhatian khusus terhadap program pengentasan kemiskinan. Maka membentuk kelembagaan di tingkat jorong, misalnya dalam bentuk badan pengentasan kemiskinan, menjadi sebuah kebutuhan. Kondisi tersebut sama pada penelitian tahun pertama dengan penelitian tahun II. b. Memberdayakan Berbasis Paruik (Kinship) 226 Pemberdayaan berbasis kerabat adalah salah satu strategi pemanfaatan remitan dari perantau untuk pengentasan kemiskinan. Ini didasarkan temuan di lapangan bahwa kecendrungan perantau memberi bantuan kepada kerabat dekat terlabih dahulu. Sistem kekerapatan keluarga luas yang berlaku pada masyarakat Minangkabau dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai berbagi antar sesama, karena selama ini kecendrungan memang membantu masyarakat pada kerabatnya terlebih dahulu. Kebiasaan membantu kerabat terdekat (kaum) tidak perlu dirobah, tapi dikelola untuk kepentingaan masyarakat nagari, hal ini juga sejalan dengan ajaran islam bahwa yang lebih dahulu dibantu adalah kerabat terdekat. Badan bentukan masyarakat ini sebagai pengelola potensi remitan yang berasal dari kerabat masing-masing. Badan ini mesti memiliki klasifikasi keluarga miskin atas kaum di jorongnya. Lalu menjadi mediator menggali remitan yang ada di kaumnya. c. Mengelola Kompetisi Positif Hasil penelitian tahun I menemukan bahwa selama ini sumbangan perantau internasional, maupun domestik lebih banyak dalam bentuk fisik, misalnya bangunan mesjid, balai pemuda, jalan dan sarana lainnya. Terjadi semacam “perlombaan” bagi perantau baik di tingkat keluarga luas, tingkat jorong, maupun pada level nagari. Ini terbukti dari bangunan fisik yang ada, buat rumah megah tapi tidak ada penghuninya, buat pagar megah atas tanah yang tidak produktis, buat kuburan yang megah, semua itu adalah aktualisasi diri atas keberhasilan seorang perantau. Hasil FGD pada penelitian ini dengan tokoh masyarakat nagari bahwa ini suatu potensi yang dapat dimanfaatkan secara positif menggali potensi remitan dari perantau. Nagari, sebagai badan koordinasi menyediakan data keluarga miskin setiap kaum, lalu memberikan kepada badan yang ada di jorong untuk mengelolanya. Badan ini hanya meminta perantau membantu keluarga yang ada pada kaumnya terlebih dahulu, kecuali bagi yang tidak ada lagi kerabat dekat yang membutuhkan bantuan. Badan pengentasan kemiskinan mencari media aktualisasi diri para perantau untuk menymbang dengan acara yang biasa dilakukan, misalnya acara lelang kue, acara badoncek untuk padang pariaman, dan acara lain untuk daerah lain. Hal ini akan mengeliminir kekuatiran perantau menymbang, kalau sumbangan itu tidak sampai kepada kerabatnya. Bagi nagari yang terpenting adalah angka kemiskinan berkurang, sehingga nagari hanya merancang program yang diperuntukan bagi kaum yang tidak ada perantaunya berpotensi (yang kaya). 5.KESIMPULAN Bila dilihat dari proses pengiriman remitan oleh migran ke kampung halamannya, program pemberdayaan menjadi strategi yang tepat mmendukung keberlanjutan program. Hal ini dapat dilihat dari proses pengiriman remitan oleh migran internasional asal Sumatera Barat dalam dua bentuk, pertama uang yang dikirim untuk kebutuhan keluarga, kedua uang juga dikirim untuk pembangunan kampung halaman. Untuk keluarga juga tidak hanya untuk keluarga inti, tapi juga untuk keluarga luas. Keterlibatan institusi lokal dalam proses pengiriman tersebut dapat dibedakan atas kiriman keluarga dan kiriman untuk pembangunan. Di tingkat keluarga pihak yang terlibat adalah keluarga inti samapai keluarga luas, namun keluarga luas seperti mamak kaum hanya mengetahui, tidak terlibat dalam pengelolaan penggunaan uang tersebut. Namun jika ada pembangunan rumah gadang kaum oleh seorang perantau, maka mamak dan ninik mamak terlibat langsung dalam hal ini. Hal ini karena menyangkut kepentingan adat seperti, tanah dan nilai-nilai dari rumah gadang kaum itu sendiri. Di tingkat institusi keterlibatan tokoh masyarakat formal dan informal pada kiriman yang ditujukan untuk pembangunan kampung halaman, baik bangunan fisik maupun melaksanakan sebuah kegiatan. Ikatan emosional perantau ada pada level jorong, 227 bukan nagari, maka pengelolaan remitan untuk pembangunan seyogyanya dilakukan di tingkat jorong. Maka perlu diberdayakan organisasi pengelola di tingkat jorong, dan Nagari bertidak sebagai badan koordinasi saja. Organisasi pengelola melakukan pemberdayaan terhadap keluarga migran, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan di nagari. Pemanfaatan remitan dilakukan dengan menangkap peluang atas nilai kompetisi dan aktualisasi diri perantau terhadap kampung halaman. Pengelolaan Remitan migran Internasional tidak bisa dipisahkan dengan remitan perantau domestik, tapi merupakan satu kesatuan pengelolaannya. Terakhir diucapkan terima kasih kepada DP2M Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikannTinggi yang telah membiayai riset ini. Tanpa dukungan dana dari DP2M tentu saja penelitian ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini. 6.DAFTAR PUSTAKA Adams , Jr. Richard, 1991. “The Economic Uses and Impact of International Remittances in Rural Egypt”. Economic Development and Cultural Change, 39: 695-722. Adams, Richard H. Jr. “International Migration, Remittances and The Brain Drain: A Study of 24 Labor Exporting Countries”. World Bank Policy Research Working Paper 3069, Washington, DC. Bridi, H. 2005. “Consequenquences of Labour Migration for The Developing Countries Management of Remittances. World Bank Brusse;s Office. Cattaneo C. 2005. “International Migration and Proverty, Cross-Country Analysis” Chami, Ralp, Connel Fullenkamp dan Samir Jahjah. 2005. Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development”. IMF Staff Papers, Vol. 52. No. 1 International Monetery Fund. Connel, J. 1980. “Remmitances and Rural Development: Migration, Dependency and Inequality in The South Pacific. Occasional Paper No.22. The Australian National University. Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage Publication. Curson, P. 1983. “Remmitances and Migration-The Commerce of Movement”. Population Demography, Vol.3, April; 77-95 De Haas, Hein. 2007. “ Remittances, Migration and Poverty Reduction, paper commissioned by DFID London, November. Effendi, Tadjuddin, Noer. 1995. “Suber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan”. Tiara Wacana. Yogyakarta. Goma. Johana Naomi. 1993. “Mobilitas Tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya Terhadap Daerah Asal. Studi Kasus Desa Neleren, Kecamatan Adonara. Kabupaten Flores Timur”. Yogyakarta: Tesis S2 UGM. Hugo., Grame. J. 1978. “Population Mobility in West Java”. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Indraddin. 2011. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari, Padang : Jurnal Sosiologi Andalas volume IX nomor 1. _________ 2014. Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Optimalisasi Pemanfaatan Remitan Migran Internasional, FISIP Unand; Prosiding Seminar Lee. Everett. 1995. “Suatu Teori Migrasi”. Terjemahan Hans Daeng. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Lucas. REB. Dkk. 1985. “Motivation to Remit: Evidence from Botswana”. Journal of Political Economy, 93 (5); 901-918. 228 Mabougunje. Akin. L. 1970. “System Approach to a theory of rural-urban Migration”. Geographical Analysis. Vol.2:1-8. Mantra. Ida Bagoes. 1994. “Mobilitas Sirkuler dan Pembangunan Daerah Asal”. Warta Demografi. Vol.3; 33-40 Nugroho, Wahyu. 2006. “Analisa Dampak Remitan Tenaga Kerja Wanita Terhadap Pengembangan Desa (Studi Kasus di Desa Budiharja, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung. Tesis Puri. Shivani. Ritzema. Tineke. 1999. “Migrant Worker Remittances, Micro-Finance and The Informal Economy: Prospects and Issue” Working Paper 21. International :Labour Orgaization. Setiadi. 1999. “Konteks Sosiokultural Migrasi Internasional: Kasus do Lewolotok, Flores TImur. Buletin Penelitian Kebijakan Kepndudukan “Populasi, Vol. 10. No. 2 pp. 17-38. Stark. Oded. 1991. “The Migration of Labor”. Cambridge. Brasil Backwell Sorensen. Nina Nyberg. 2004. The Development Dimension Of Remittances”, Migration Policy Research IOM Working Papers Series No. 1 June. Tjiptoheriyanto, Priyono. 1997. “Migran Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan)”. Serial Diskusi ke VII. Diskusi “Peta Permasalahan Perempuan Pekerja Migran”. Jakarta 5 Maret. 1997. Afkar. Vol. IV. No.1. Todaro, Michel P. 1996. “Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang”. PPK UGM. Yusuf, Iwan Awaluddin (2012). ”Memahami Focus Group Discussion (FGD)”, http://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dankonsumtivisme-pada-remaja/tangal akses 19-3-2012. Wiyono.NH. 1994. “Mobilitas Tenaga Kerja dan Globalisasi”. Warta Demografi. Vol.3;813 Wood.Charles H. “Equilibarium and Historical-Structural Perspective Migration”. International Migration Review. Vol.2; 298-319. SOLIDARITAS SOSIAL KOMUNITAS NELAYAN ANTAR ETNIK DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si32 Titi Stiawati, S.Sos., M.Si33 Abstrak Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya, mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai dan hidup dari berbagai suku bangsa serta kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat dan suku bangsanya masing-masing yang 32 33 Dosen Sosiologi Fisip Untirta Dosen Fisp Untirta 229 membutuhkan hubungan sosial yang erat. Penelitian ini terfokus pada karakteristik komunitas nelayan antar etnik, dan proses solidaritas sosial pada komunitas nelayan antar etnik, serta bentuk solidaritas sosial komunitas nelayan antar etnik dalam penerapan teknologi untuk kehidupan sosial ekonomi di Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Metode Penelitian adalah kulaitatif dan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriktif kualitatif. Informan penelitian adalah komunitas nelayan etnik Jawa, Sunda dan Bugis yang bermukim di pesisir perkampungan Labuan dan Binuangen.Hasil penelitian ditemukan bahwa Karasteristik komunitas nelayan antar etnik memiliki kesamaan dalam hal wilayah pemukiman, pola hidup dan juga dalam hal tradisi sebagai komunitas nelayan terutama dalam hal melakukan aktifitas menangkap ikan di laut. Proses soslidaritas sosial dilakukan melalui adaptasi nilai-nilai sosial dan budaya dengan saling memahami serta tumbuh saling pengertian atas nilai-nilai yang diyakininya. Terjadinya solidaritas dilakukan melalui beberapa faktor yakni kegiatan perekonomian, pola kekerabatan dan kedekatan berdasarkan pemukiman, perkawinan campur, nilai-nilai ritual dan kepercayaan melalui hari-hari besar keagamaan. Kata Kunci: Komunitas Nelayan, Solidaritas Sosial, Etnik Abstrack Fishermen are a group of people whose lives depend directly on the sea, either by means catching or farming, they generally live on the beach and life of many races and cultures prevailing in the society and each tribe. This study focused on the characteristics of the fishing communities of ethnic, and social solidarity in the process of inter-ethnic community of fishermen and fishing communities form of social solidarity between ethnic groups in the application of technology for social and economic life in Panimbang Pandeglang Banten Province. Methods The study is qualitative and retrieval of data through observation, interview and documentation. Analysis of data using qualitative deskriktif. The informants are the fishing communities of ethnic Javanese, Sundanese and Bugis who settled in the coastal village of Labuan and Binuangen. The Research found that ethnic characteristics fishing communities have in common in terms of residential areas, the pattern of life and also in terms of tradition as a fishing community, especially in terms of doing activity catch fish in the sea. The process of social soslidaritas done through the adaptation of social values and cultural understanding as well as the growing. The occurrence of solidarity carried out by several factors namely economic activities, patterns of kinship and closeness based on settlements, intermarriage, values, rituals and beliefs through religious holy days. Keywords: The Fishing Community, Social Solidarity, Ethnic 1. PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagio state), yang jumlahnya adalah 17.508 pulau, memiliki luas wilayah perairan lautnya sekitar 5,8 juta Km persegi, dengan total garis pantai sepanjang 81.000 Kilometer (BPPT-Wanhankamnas, 1996: 12), demikian halnya Banten merupakan wilayah maritim terbentam dari teluk Jakarta hingga perbatasan jawa Barat. Kehadiran masyarakat menetap dalam kondisi multikultur dan berakulturasi dengan menghargai prularisme sebagai keragaman budaya untuk tetap di lestarikan. Kemajemukan di tandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai 230 cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara etnik yang satu dengan etnik lainnya. Mata pencaharian hidup pun berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan musim yang menyebabkan masyarakat agraris dan menjadi nelayan. Tantangan musim untuk mencari nafkah juga menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan oleh komunitas petani dan nelayan dengan berbagai strategi serta teknologi untuk mengatasinya. Komunitas nelayan masih memiliki ketergantungan terhadap lingkungan alam antara musim kemarau dan musim penghujan. Keeratan atas ketergantungan dengan lingkungan alam, maka dibutuhkan keseimbangan. Artinya kalau lingkungan alam terganggu, maka lahan pencaharian utama tertutup dan nelayan pun tidak dapat mencari ikan. Akibatnya tidak ada pemasukan pendapatan bagi rumah tangganya. Jika keadaan demikian itu terjadi, maka kelangsungan kehidupan ekonomi secara internal rumah tangga nelayan pun ikut terganggu. Kondisi ini mendorong nelayan harus menyesuaikan kegiatan hidupnya dengan kondisi yang serba terbatas, baik yang menyangkut hubungan secara sosial (eksternal) maupun secara kekeluargaan (internal) Salah satu aspek penting untuk mendukung meningkatkan kehidupan ekonomi nelayan yakni masuknya penerapan teknologi dibidang perikanan laut. Hal itu terkait, proses substitusi teknik produksi, dari cara-cara tradisional beralih kepada cara-cara rasional. Perubahan ini merupakan bagian dari keseluruhan proses transformasi kebudayaan masyarakat nelayan dengan segala konsekuensinya. Masuknya unsur teknologi pada komunitas nelayan, secara umum kehidupan nelayan sangat tergantung pada teknologi untuk menggali sumber kekayaan laut. Akibat kepemilikan demikian, maka menimbulkan dampak sosial lebih besar dan menyebabkan perbedaan antara yang mampu memiliki teknologi dengan yang tidak mampu memiliki teknologi. Salah satu perbedaan yang ditonjolkan yakni terkait dari segi kemampuan untuk memperoleh hasil. Kehadiran teknologi sepenuhnya dipergunakan untuk memperebutkan sumber kekayaan alam secara terbuka. Dampak dari hal itu, memunculkan persaingan dalam artian bahwa siapa yang mampu memiliki dan memanfaatkan teknologi akan semakin memperoleh hasil yang lebih banyak. Pandangan semacam itu, bahwa kehadiran teknologi dalam suatu komunitas nelayan hanya lebih cenderung di peruntukkan untuk peningkatan dari segi ekonomi. Dari segi aspek sosial budaya yang telah terjalin dalam waktu cukup lama tidak menjadi lagi perekat dalam hubungan antara komunitas yang terlibat di dalamnya. Kekuatan telah menjadi milik masyarakat secara pribadi dan memiliki nilai moral, terkait hal itu Emmerson (1977: 37) mengemukakan bahwa hubungan tradisional menempatkan unsur ikatan ekonomi pada peringkat sekunder. Secara realitas bahwa nelayan meminjam uang kepada juragan dan cara pengembaliannya tidak dihitung dengan cara transaksi, yang pasti dan kadang tidak dikembalikan dalam bentuk uang tapi bisa dalam bentuk barang. Perkembangan penggunaan teknologi membuat perbedaan komunitas nelayan dan ditentukan oleh kehidupannya. Menurut Koentjaraningrat (1972: 32) mata pencaharian nelayan lebih banyak tergantung pada perkembangan teknologi. Sedangkan Suparlan (1989:4) perbedaan tersebut pada hakekatnya adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing. Puncak-puncak kebudayaan tersebut adalah konfigurasi yang masing-masing kebudayaan memperlihatkan adanya pinsip-prinsip kesamaan dan saling penyesuaian satu dengan lainnya sehingga menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional. Selanjutnya, terdapat kebudayaan umum yang bersifat lokal yang dapat dilihat sebagai sebuah wadah untuk mengakomodasi proses pembauran atau asimilasi dan proses akulturasi, yang di antara kebudayaankebudayaan itu saling berbeda wilayah atau dikelilingi wilayah kebudayaan umum yang bersifat lokal. 231 Berdasasarkan observasi pendahuluan bahwa lokasi penelitian memiliki karakteristik yang unik, karena komunitas nelayan yang bermukim dipesisir pantai Kecamatan Panimbang hidup dan menetap komunitas nelayan dari berbagai etnis yang hidup berdampingan berdasarkan dengan budayanya masing-masing. Sebagai komunitas nelayan tetap menjalankan aktifitasnya dan tidak mengganggu satu sama lainnya dan menjalin ikatan-ikatan solidaritas sosial untuk saling mendukung kegiatannya sebagai nelayan. Penelitian ini akan terfokus akan mengkaji karaktersistik nelayan antar etnis dan proses solidaritas sosial serta bentuk-bentuk solidaritas dalam penerapan teknologi untuk kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten penelitian ini terfokus pada karakteristik komunitas nelayan antar etnik, dan proses solidaritas sosial pada komunitas nelayan antar etnik, serta bentuk solidaritas sosial komunitas nelayan antar etnik dalam penerapan teknologi untuk kehidupan sosial ekonomi di Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 2. TINJAUAN PUSTAKA Komunitas Nelayan Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya, mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai Kusnadi (2005: 25) bahwa nelayan umumnya tinggal atau menetap di daerah pesisir pantai dan membentuk suatu komunitas yang disebut dengan komunitas nelayan. Mereka adalah orang-orang yang begitu gigih dan akrab dengan kehidupan di laut yang sifatnya keras. Pengetahuan tradisionalnya tentang ekologi kelautan, merupakan bagian dari kehidupan mereka yang sifatnya turun temurun. Para nelayan ini sangat percaya betapa pun kuatnya tantangan itu, laut tetap menawarkan berbagai kemungkinan serta memberikan peluang dalam mencari nafkah untuk memperolehnya dan mereka berjuang dengan penuh keyakinan, keuletan dan ketabahan serta penggunaan teknologi yang sederhana. Menurut Gordon dalam Satria (2002: 37) bahwa nelayan adalah orang yang melakukan penangkap ikan baik di perairan laut atau pun di perairan umum dengan menggunakan seperangkat alat tangkap ikan. Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkap ikan di laut. Definisi ini dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Ketika perikanan sudah mengalami berbagai perkembangan, pelaku-pelaku dalam penangkapan ikan semakin beragam statusnya. Secara sosiologis, fenomena ini merupakan konsekuensi dari adanya differensisasi sosial yang salah satunya berupa pembagian kerja atau divission of labour. Satria (2002: 53) bahwa nelayan dapat kita bagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang alatnya dioperasikan oleh orang lain. adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Solidaritas Sosial Antar Etnik Konsep solidaritas sosial dalam pembahasan ini didasarkan kepada pemikiran Emile Durkheim (dalam Johnson, 1986 :181) bahwa solidaritas menunjuk pada suatu keadaan dari hubungan antara individu, dan atau kelompok yang didasarkan pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama pula. Koentjaraningrat (1980 :164) menyatakan bahwa, solidaritas adalah suatu bentuk 232 kerja sama pada masyarakat yang meliputi aktivitas gotong royong, tolong menolong dan musyawarah, dan aktivitas ini berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat, solidaritas sebagai bentuk kekuatan internal berkembang menjadi dua bagian dan mempunyai ciri-ciri yang berbeda yakni solidaritas mekanik dan organik. Durkheim (dalam Johnson, 1986: 193) menyatakan bahwa solidaritas mekanik adalah suatu solidaritas yang didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen. Solidaritas organik muncul akibat pembagian kerja yang bertambah besar, dan solidaritas ini didasarkan kepada tingkat saling ketergantungan yang tinggi sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Durkheim (dalam Lawang, 1986: 177-178) pandangannya tentang kehidupan masyarakat mengemukakan konsep teorinya tentang fakta sosial dengan karakteristikkarakteristik sebagai berikut, bahwa fakta sosial terkait (1) gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu; (2) bersifat memaksa individu; dan (3) bersifat umum tersebar dan diterima secara meluas dalam suatu masyarakat. Secara spesifikasi berbagai pengertian tentang konsep solidaritas sosial, Johnson (dalam Lawang, 1986: 181) menjelaskan istilahistilah yang berhubungan erat dengan itu misalnya integrasi sosial dan kekompakan sosial. Keberadaan masyarakat antar etnik dalam suatu lokasi itu menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang berbeda dari latar belakang asal usul dan berdasarkan sejarah keberadaan awalnya. Perbedaan itulah melahirkan sebuah keterpisahan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama yang pada akhirnya terbentuk ikatan sosial yang kuat. Modernisasi dan kehidupan sosial ekonomi Kehadiran modernisasi yang ditandai oleh pertumbuhan industri-industri besar, produksi komersial, pasar rasional dan perdagangan internasional, juga menciptakan syarat-syarat yang cocok dengan modernisasi. Abraham (1991: 11) berpandangan bahwa industrialisasi melibatkan penggunaan energi material yang banyak sekali. Suatu perubahan metode produksi dari padat karya (tenaga kerja) menjadi padat modal, suatu pergantian dalam tenaga kerja di luar produksi primer dan subsistem menjadi perusahaan sekunder dan komersial, serangkaian inovasi dan peningkatan waktu luang dan jasa sosial yang bertambah. Perkembangan industrialisasi kaitannya dengan perkembangan produksi masyarakat, dalam konsep Marx lebih cenderung menganalisis berdasarkan pendekatan sejarah, tingkatan tersebut digambarkan pada jaman kuno penguasaan produksi berada ditangan pemilik pribadi, akan tetapi tetap terkurung di dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi yang terbatas. Di dalam abad-abad pertengahan, pemilikan bergerak melalui beberapa tahapan dari tanah milik feodal ke milik koperasi yang bisa dipindahkan, dan akhirnya melahirkan kapital yang ditanamkan didalam perpabrikan di kota-kota. Pada masyarakat kuno ataupun pada abad-abad pertengahan, pemilikan itu terus terikat sebagian besar kepada masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan yang pola-pola perilaku dan kebudayaan individu berubah, dari yang tradisional ke masa lalu dan sekarang ke suatu yang lebih kompleks, teknologi yang lebih rumit dan berorientasi ke masa yang akan datang. Perubahan karakteristik masyarakat kaitannya dengan kehadiran industrialisasi yang ditonjolkan. Menurut pandangan Rostow (1966) yakni ditandai dengan (1) tumbuhnya industri skala besar; (2) industri berat, yang menimbulkan tumbuhnya perusahaan dan industri-industri berat; (3) adanya trust dan monopoli yang menjadi ciri umum dari organisasi perusahaan yang memberikan keuntungan ekonomi. 233 Penerapan Teknologi Pertumbuhan atau kemajuan ekonomi yang ditandai oleh tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi teknologi, intensitas modal yang makin besar dan organisasi birokrasi yang rasional mencakup pembentukan sistem pertukaran moneter, peningkatan tingkat keterampilan yang dibutuhkan melalui teknokrasi, mekanisasi, otomasi dan akibat perpindahan tenaga kerja, penghitungan biaya secara rasional, spesialisasi okupasi yang makin besar dan spesifikasi fungsional. Pola-pola tabungan dan investasi dan alat-alat transportasi dan komunikasi yang makin cepat yang memudahkan turut serta dalam pemasaran, mobilitas tenaga kerja, distribusi barang dan perubahan pola konsumsi. Modernisasi ekonomi, asumsinya diikuti dengan perluasan pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi, pembentukan modal, tingkat pendidikan yang cocok, spesialisasi ekonomi dan kecukupan bahan-bahan mentah, barang produksi dan konsumsi. Modernisasi sebagai seluruh perubahan sosial dan politik yang menyertai industrialisasi di kebanyakan negara yang menganut peradaban Barat. Modernisasi yang menyangkut pilihan dimungkinkan oleh adanya perbedaan perkembangan. Dalam konteks modernisasi ekonomi tentu saja tidak terlepas adanya non-ekonomi atau modernisasi sosial dan budaya. Secara kerangka konseptual mencakup modernisasi politik dan psikologis, modernisasi sosial meliputi perubahan dalam atribut-atribut sistematik, pola-pola kelembagaan dan peranan-peranan status dalam struktur sosial masyarakat sedang berkembang. Unsur-unsur pokok modernisasi sosial mencakup perubahan sosial yang terencana, sekularisme, perubahan sikap dan tingkah laku, revolusi pengetahuan melalui perluasan sarana komunikasi, instrumen hubungan sosial dan keharusan kontraktual, diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional. Untuk mencapai modernisasi berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi, maka sebagian besar nilai dan sikap berkaitan dengan masalah komitmen. Masalah komitemen penerimaan ideologi nasional,keinginan untuk menjadi lebih mobil, menyetujui normanorma rasional sekuler. Hal ini semuanya pada hakekatnya berkaitan dengan komitmen terhadap modernisasi. Untuk itu memantapkan komitmen terhadap modernisasi ini mungkin digunakan berbagai metode seperti ideologi, perubahan struktural dan aktivitas simbolis. Dengan demikian, tanpa komitmen modernisasi barangkali tidak akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi menuntut kehadiran industri, namun kehadiran industri dan teknologi modern menuntut kemampuan manusia, walaupun kehadiran teknologi itu sendiri merupakan hasil ciptaan dan resultante usaha manusia. Sudah barang tentu manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menciptakan karya besar itu, walaupun umumnya kehadiran dari generasi yang terbatas jumlahnya namun sangat dibutuhkan dalam konteks era industrialisasi. Dalam kaitan ini, diperlukan ilmu pengetahuan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menemukan, melaksanakan, serta pembaharuan dalam segala aspek bidang terutama terciptanya kehidupan sosial yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Perubahan Sosial Dan Budaya Proses perubahan sosial secara umum, menurut Haferkamp dan Smelser (1992 :2) bahwa terfokus pada tiga unsur utama yang berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, determinan struktural; kedua, proses dan mekanisme, dan ketiga, arah dan konsekuensi perubahan. Tarkait hal itu Haferkamp lebih lanjut bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dikategorikan sebagai perubahan yang terjadi karena disengaja atau direncanakan. Artinya bahwa salah satu faktor penyebab perubahan adalah faktor eksternal yang dibawa dan dikomunikasikan melalui agen-agen perubahan dari luar masyarakat. 234 Dalam perubahan sosial yang direncanakan terkandung ide-ide baru yang disebarkan di tengah masyarakat (inovasi), inovasi akan membawa pada perubahan, baik yang bersifat fositif dalam arti membawa pada hal-hal yang lebih baik (progress), maupun yang bersifat negatif yang dapat merugikan anggota masyarakat (regress). Realitas tersebut secara kontekstual bahwa munculnya industrialisasi dalam suatu kawasan umumnya diawali dengan pemanfaatan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan industri, baik untuk keperluan industri maupun untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya pergeseran alih fungsi lahan yang bemuara pada perubahan pola pekerjaan yang dulunya terkonsentrasi dalam sektor pertanian beralih keberbagai kesempatan dan peluang kerja yang tersedia, baik dalam sektor industri maupun sektor lain yang terkait dengan kehadiran industri. Lauer (1989:212) bahwa kehadiran industrialisasi dalam suatu kawasan dengan indikasi membawa konsekuensi perubahan terhadap manusia. sejarah kehidupan selalu berupaya memelihara dan menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang selalu mengalami perubahan karena ditemukannya teknologi. hal itu dimungkinkan karena manusia sebagai makhluk hidup pada hakekatnya mempunyai kelenturan. Kelenturan ini menyebabkan manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makin besar kemampuan adaptasi, makin besar kemantapan kelangsungan hidupnya. Hal itu terimplementasikan bahwa kehadiran industrialisasi melahirkan keberagaman jenis pekerjaan yang tersedia. Sehubungan kehadiran industri itu pula, akan memberi banyak peluang dan kesempatan berusaha. Dengan demikian kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat terbuka lebar, dan ini dapat berimplikasi pada bidang-bidang lain, seperti halnya peningkatan pendidikan masyarakat, yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial masyarakat. 3. METODE PENELITIAN Desain penelitian ini adalah deskriktif analitik, yang berusaha menemukan dan mendeskripsikan tentang komunitas nelayan antar etnik kaitannya solidaritas sosial dalam penerapan teknologi untuk kehidupan sosial ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menfokuskan pada sebuah peristiwa berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Menurut Brannen (1997), pendekatan kualitatif mengungkap makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Penentuan informan diperoleh dari kunjungan lapangan yang di lakukan di lokasi-lokasi komunitas nelayan antar etnik. Informan dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni kelompok nelayan antar etnik yang bermukim di Kecamatan Panimbang yang terdiri dari nelayan etnik Jawa, etnik Sunda dan etnik Bugis. Teknik pengumpulan data dilakukukan melalui pengamatan berperan-serta dengan ikut terlibat dalam hubungan sosial nelayan secara internal dengan memiliki keterkaitan langsung pada aktivitasnya. Kemudian pengamatan berperan-serta dilakukan hingga pada aktivitas proses interaksi yang dilakukan baik dalam aktivitasnya maupun dalm kesehariannya selama berada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu di lakukan Wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam konstruksi realitas. Pertanyaan dibuat luwes serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, agar baik peneliti maupun informan dapat saling memahami. Selain wawancara dilakukan pula dokumetasi dalam berbagai kegiatan baik yang sedang berlangsung maupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan. Analisa data dilakuka; Pertama, Kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Kedua, 235 Penyajian data, dalam kegiatan ini penulis menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik dipisahkan Ketiga, Data yang telah dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik, kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan mana data belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Keempat, Setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai kepada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, khusunya di pemukiman komunitas Nelayan antar etnik. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Masyarakat Pesisir Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya (Dahuri dkk. 2001: 5). Masyarakat peisir, sebagain besar menggantungkan hidupnya dari hasil biota laut dan bekerja sebagai nelayan. Kehidupan sebagai nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah menangkap ikan berdasarkan pada musim yang sedang berjalan. Profesi sebagai nelayan, merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari bagi komunitas nelayan, dan hasil tangkapan tersebut, sebahagian untuk dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya dan atau dijual seluruhnya. Biasanya nelayan akan berangkat kelaut pada sore hari setelah sekitar jam 15.00 Wib dan biasanya nelayan kembali mendarat pada pagi hari sekitar jam 07.00 wib dan atau jam 09.00 wib. Bagi komunitas nelayan di perkampungan Binuangen, selalu meyakini bahwa hari jumat merupakan hari sakral yang tidak boleh melaut. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan, namun masih banyak yang meyakini bahwa hari jumat merupakan hari keagamaan yaitu masuk jumatan. Perkampungan nelayan di Panimbang, merupakan perkampungan yang memiliki jumlah sekitar kurang lebih 200 KK yang berada di sepanjang pesisi pantai. Perkampungan nelayan yang padat diperkampungan nelayan, namun memiliki dampak sosial tersendiri, diantaranya adalah kurangnya fasilitas lingkungan yang memadai serta tingkat kebisingan yang cukup sesak. Kondiai perumahan yang sangat padat, sebenarnya bagi masyarakat tidak menjadi persoalan yang serius, namun bagi warga yang berkunjung ke perkampungan sangat tidak nyaman, karena adanya perbedaan kultur dan pola hidup. Lamanya berinteraksi dan menetap, bagi komunitas nelayan di Panimbang, tidak hanya tercipta hidup berdekatan namun sangat akrab dan saling memelihara kondisi lingkungan sekitarnya. Pemeliharaan kondisi lingkungan sosial sangat penting agar tetap terbangun hubungan baik sesama manusia, walaupun berbeda suku dan latar belakangnya. Kesadaran akan lingkungan tempat tinggal yang kondusif, maka komunitas nelayan di binuangen membentuk berbaga kegiatan untuk tetap harmonis, baik dalam bidang olahraga maupun dalm bidang keagamaan. Dalam bidang olahraga, melakukan kegiatan sepak bola antar rukun tetangga maupun kegiatan bola voly dilokasi lapangan yang telah di sediakan di wilayah pesisir pantai. Sedangkan kegiatan keagamaan, dilakukan kegiatan pengajian ibu-ibu secara bergiliran dari rumah penduduk yang dilaksanakan pengajian bulanan dan bergantian menjadi tuan rumah. Pola kekerabatan dan perkampungan yang padat, maka pola kedekatan terbangun dengan baik, maka dari segi perkembangan berita diperkampungan memudahkan penyebaran informasi apapun. Misalnya kejadian-kejadian yang menyangkut pergeseran moralitas maupun pelanggaran etika yang tidak sesuai dengan kebiasaan maka akan mudah diketahui oleh penduduk setempat. Pola keakraban yang terjadi selama ini sangat sulit 236 menyimpan rahasia pribadi atau rumah tangga karena yang ada hanyalah rahasia umum, begitu pun halnya dengan berita-berita kesuksesan maupun kesedihan semuanya menjadi konsumsi masyarakat kampung. Kondisi sosial budaya masyarakat lokal dengan komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda sebelum kedatangan masyarakat transmigran dengan setelah kedatangan para transmigran mengalami pergeseran-pergeseran melalui proses asimilasi dan akulturasi dan kemudian berintegrasi dengan masyarakat lokal. Pendatang mengalami proses perubahan setelah berinteraksi lama dan intens satu sama lainnya. Pola hidupnya mengalami penyesuaian dan penyelarasan yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada mereka seperti pada cara mereka berkomunikasi, model rumah yang mereka buat dan proses pernikahan campur diantara mereka. Adanya pernikahan diantara mereka memungkinkan terjadinya pertukaran nilai antara kultur dari masyarakat asli dengan kultur yang dibawa oleh para transmigran. Proses penyatuan antar Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda merupakan suatu proses dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan. Karakteristik Solidaritas Sosial Komunitas nelayan yang bediam di wilayah perkampungan pessir, sebagaimana masyarakat lainnya melakukan interaksi sosial dan proses sosial berbasis kebutuhan hidup dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hidup secara berdampingan dan saling menyapa satu sama lainnya seakan-akan tidak ada batas yang memisahkan diantara mereka. Kesamaan mata penaharian sebagai nelayan, membuat komunitas nelayan di Panimbang melakukan interaksi sosial dengan membangun kerjasama dan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya sebagai komunitas nelayan. Kehidupan kolektifitas dan kebersamaan senasib merupakan gambaran fenomena sosial yang terjadi di Panimbang dan proses sosial berjalan dalam sebuah sistem kerja bersama untuk mencapai tujuan hidupnya sebagai nelayan. Kesadaran kolektivitas merupakan pemandangan yang sering di saksikan dalam melakukan pelayaran dan juga dalam membenahi alat tangkap pada saat kembali dalam menjalankan aktifitasnya. Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan, komunitas nelayan di Panimbang lebih mengedepankan pendekatan kebersamaan sebagai sistem, dan selanjutnya dalam menjalankan aktifitasnya modal kepercayaan dijadikan sebagai modal untuk saling bekerjasama satu sama lainnya. Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda yang hidup Di Pesisir Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan pembauran dari masyarakat lokal. Komunitas lokal yang berdatangan dari berbagai antar etnik itulah, secara pendekatan kebudayaan mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan asal-usul dan latar belakang kebudayaan itu, telah mempengaruhi pola tingkah laku berdasarkan wiayah dan dialek asal-usulnya. Komunitas nelayan di Panimbang dengan latar belakang yang berbeda-beda itu, sehingga menjadi dinamika yang sangat menarik dan hingga saat ini tetap melekat pada masyarakat pendatang yang bermukim di Panimbang. Sebagai masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan sudah dianggap sebagai dinamika dalam berinteraksi bagi masyarakat yang berdiam di Panimbang, sudah menjadi kebiasaa-kebiasaan dan saling mengakui bahwa sesama 237 pendatang memiliki latar belakang budaya dan asal usul yang berbeda. Kesadaran akan latar belakang yang berbeda itu sangat mudah diperhatikan melalui tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari pada saat hidup berkelompok dan melakukan sosialisasi satu sama lainnya. Terjadinya dinamika hidup perbedaan itu, bagi komunitas nelayan yang bermukim di Panimbang sudah dialami secara turun menurun dan bahakn dari berbagai sumber dari informan terkait kedatangan pendahulunya, bahwa sebenarnya mereka sudah hidup menetap dalam dekade dari generasi ke generasi. Informan dari antar etnik Bagis mengunkapkan bahwa kedatangan masyarakat Bugis di Panimbang bermula pada tahun 1960-an dan bahkan ada informasi bahwa pendatang Bugis sekitar era akhir tahun 1950an. Secara pengakuan oleh beberapa masyarakat berasal dari Bugis, memperkirakan bahwa secara pastinya menetap di Panimbang sudah hidup generasi yang ketiga saat ini yang bernata pencaharian sebagai nelayan. Tradisi sebagai pekerja atau nelayan musiman, bagi antar etnik Jawa sampai saat ini masih terdapat komunitas yang hanya menggantungkan hidupnya sebagai buruh nelayan musiaman di perkampungan Panimbang. Dalam perkembangan dan dinamika tuntutan hdup, maka dulunya sebagai buruh nelayan musiman, telah mengalami dinamika sosial yang menuntut mereka untuk menyewa dan bahkan ada niatan untuk membeli perahu dan alat tangkap. Melalui kepemilikan alat tangkap itulah, maka mau tidak mau atau suka atau tidak suka komunitas nelayan yang telah memiliki alat tangkap itu merasa berkewajiban untuk menjaga dan menjalankan alat tangkapnya. Komunitas yang bersal dari etnik Jawa yang menetap sudah cukup lama yaitu sekiar tahun 1970-an. Kedatangan mereka sebenarnya diawali sebagai buruh nelayan, namun dalam perkembangannya, karena desakan tuntutan hidup maka mereka menetap sebagai nelayan. Berbagai perbedaan-perbedaan dan perubahan yang tampak pada kondisi sekarang, merupakan hasil dari suatu perubahan sosial budaya yang telah terjadi dan dialami oleh mereka sejak awal. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang perubahan itu. Perubahan strukur sosial budaya yang terjadi sering saling memahami yang akan mengarah pada stuktur masyarakat yang berkelanjutan. Kehadiran komuitas nelayan yang berasal dari antar etnik Sunda, sebagain besar penduduk lokal yang sudah menetap sudah cukup lama. Komunitas nelayan berasal dari antar etnik Sunda itu, sebenarnya juga berasal dari luar Banten misalnya dari Jawa Barat. Komunitas antar etnik sunda itu, ada yang berasal dari Cirebon dan Sukabumi. Namun karena kesamaan bahasa dan budaya, maka hampir sulit dibedakan antara antar etnik sunda pendatang dengan antar etnik sunda yang berasal dari Banten. Profesi sebagai nelayan bagi komunitas nelayan antar etnik sunda, sebenarnya merupakan pekerjaan yang ditekuninya secara turun menurun. Hampir apa yang dialami antar etnik Jawa dan Bugis, bahwa bagi komunitas nelayan yang menetap di pesisir Panimbang, sebagain besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan, baik nelayan pemilik alat tangkap maupun sebagai buruh nelayan yang tidak memiliki alat tangkap, namun diberikan kepercayaan untuk mengelola milik orang lain. Perubahan sistem nilai budaya yang dianut dan dimengerti oleh orang yang mendukung budaya itu. Demikian halnya pada masyarakat yang bermukim di pesisir Panimbang memiliki ikatan-ikatan kultur secara khas berdasarkan latar belakang asal usulnya. Kepemilikan secara individu maupun secara sosial terkait karakteristik itu, lebih terlihat pada saat sosialisasi atau saling menyapa satu sama lainnya. Secara fisik sebenarnya sudah bisa dikenal asal usul sesorang bahwa mereka berasal darimana dan antar etnik mana. Secara penataan pemukiman, bagi komunitas nelayan yang bermukim di Perkampungan nelayan Panimbang memiliki blok pemukiman berdasarkan kesukuan. 238 Pemukiman yang dibuat secara terpisah, sebenarnya menurut informan tidak ada unsul saling tidak menghargai satu etnik dengan antar etnik lainnya. lagi pula pemukiman antar etnik sebenarnya dibuat pada masa lalu berdasarkan kesamaan komunikasi, sehingga saling memudahkan dalam bekerjasama. Sebagaimana terungkap diungkapkan oleh MHR (59 th) beliau berasal dari etnik Jawa bahwa : Setiap masyarakat yang bermukim di Panimbang, memiliki masing-masing latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda, juga logat dan dialek yang berbeda-beda berdasarkan asal usul kami. Tetapi pembedaan latar belakang itu, tidak akan mengurangi kebesamaan dalam kehidupan maupun bermatapencaharian dengan para pendatang lainnya yang sudah sejak lama kami bersama-sama hidup di Panimbang ini. Walaupun kami berbeda asal usul dan latar belakang kampung halaman, namun perbedaan nilai-nilai yang kita yakini tidak membuat kita saling mencurigai Berdasarkan hasil wawancara itu terungkap bahwa sebenarnya masyarakat yang bermukim di Panimbang, sebenarnya memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Walaupun berbeda asal usul mereka, tetap menjunjung tinggi dinamika yang ada di perkampungan Panimbang. Kesadaran komitmen pengakuan perbedaan itupula, sehingga tidak tapak adanya ketersinggungan secara individu maupun kelompok. Kehidupan berdampingan melalui kebesamaan dalam kehidupan maupun bermatapencaharian dengan para pendatang lainnya yang sudah sejak lama bersama-sama hidup di perkampungan pesisir Panimbang. Komitmen secara berkelompok sangat dikuatkan, maka berbeda asal usul dan latar belakang kampung halaman serta perbedaan nilai-nilai tidak membuat ada sikap saling mencurigai. Masyarakat yang bermukim di Panimbang, perbedaan etnis tidak menjadikan sebuah jurang pemisah dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Walaupun berbagai etnik itu memiliki masing-masing latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda, namun tidak menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Sebagai bangsa yang berbeda-beda, tentunya juga logat dan dialek yang berbeda-beda berdasarkan asal usul dimana masyarakat itu berasal. Tetapi pembedaan latar belakang itu, tidak akan mengurangi kebersamaan dalam kehidupan maupun bermatapencaharian dengan para pendatang lainnya yang sudah sekian lama hidup secara bersama-sama di Panimbang ini. Perbedaan latar belakang etnis tidak menjadi persoalan dalam menjalankan aktifitas sebagai nelayan sebagaimana ungkapan oleh etnik Bugis Bahar (43 tahun) bahwa Sebagai komunitas yang bermatapencaharian sebagai nelayan, berbagai antar etnik tetap berdampingan sebagai satu kesatuan komunitas nelayan. Walaupun sangat nampak perbedaan latar belakang asal usul keberadaan kampung halaman kami, namun tidak menjadikan alasan untuk tetap hidup berdampingan. Sebagaimana hal yang tampak bahwa kepemilikan alat tangkap bisa digunakan oleh etnis manapun saja, tanpa melihat latarbelakang. Kepercayaan diantara kami sudah menjadi bagian yang sangat terpenting dalam mempertahankan hidup yang harmonis secara berdampingan. Berdasarkan ungkapan di atas sejalan dengan teori fungsional struktural yang menyatakan masyarakat harus dilihat sebagai satu sistem yang komponennya berhubungan, bergantung, dalam saling mengait yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk equilibrium yang bersifat dinamis. Apabila ada pertentangan, akan muncul nilai budaya yang akan mengintegrasikannya. Sangat terlihat dalam pola bermasyarakat yang terjadi di Kecamatan Panimbang maupung di Labuan, baik masyarakat Bugis, Jawa Maupun Sunda sebagai masyarakat setempat. Kemajemukan yang meliputi agama, antar etnik, budaya dan 239 kebiasaan justru mendorong mereka menjaga kerukunan hidup diantara mereka dan berintegrasi satu sama lain. Proses Solidaritas Sosial Faktor Budaya Nilai budaya sebagai perekat diantara komunitas telah memiliki nilai-nilai yang mengatur tatanan masyarakat dalam mempertahankan komunitasnya. Melalui nilai-nilai itulah mereka saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai kesopanan itulah sebenarnya merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk di tegakkan dan dipersatukan. Kebersatuan masyarakat dalam komunitasnya akan menjadi cerminan pada saat mereka berinteraksi pada komunitas lainnya. Kekuatan budaya yang dianut masyarakat akan menjadi anutan untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya, sebagai bagian mahkluk sosial dan mahkluk yang berbudaya. Hidup dalam sebuah komunitas yang beraneka ragam akan sangat mudah melakukan hubunganan yang sosial yang lainnya, sekiranya saling memperkuat nilai-nilai pada komunitasnya. Nilai-nilai budaya yang dianut pada komunitas masyarakat secara berbeda-beda, namun menjadi cerminan untuk mengakurkan dirinya secara individu dan secara kolektif sebagai masyarakat yang menyatu satu sam lain. Kebersatuan masyarakat antar etnis juga sebenarnya ditunjang oleh adanya ikatan-ikatan simpul budaya melalui kebiasaankebiasaan secara turun temurun yang dijadikan pegangan dalam hidupnya. Sebuah komunitas akan dapat bertahan dan dapat berinteraksi dengan baik ketika diperekat oleh sistim dan kebiasaan-kebiasan yang telah disepakati secara turun temurun. Sebagaimana diungkapkan oleh HAN (57 tahun) etnis Bugis yang menetap di Panimbang bahwa: Keberadaan komunitas antar etnis Bugis dan Jawa serta Sunda di Panimbang masing-masing memiliki sistem dan aturan masing-masing secara internal. Menjadikan sebagai masyarakat yang saling mengikatkan diri dalam komunitas yang hidup dengan kemajemukan di Panimbang dengan hidup berdampingan dengan kegiatan sebagai nelayan dan maupun bukan nelayan tetap merasa satu kesatuan serta ikatan yang memiliki kesamaan pekerjaan dan maupun yang tidak memiliki kesamaan pekerjaan. Hal yang dapat mempersatukan dalam hidup berdampingan adalah nilai-nilai pola hidup yang mereka pegang secara bersama-sama dan dapat menjadikan sebagai modal untuk membina ikatan sosial dengan masyarakat sekitarnya. (wawancara 25 Mei 2013) Berdasarkan hasil wawancara itu, tergambarkan bahwa keberadaan komunitas antar etnis Bugis dan Jawa serta Sunda di perkampungan nelayan di Panimbang dalam melakukan interaksi telah memiliki ikatan-ikatan sosial dalam mempertahankan hidupnya. Berdasarkan nilai itulah menjadi pedomana dan berlaku surut bagi masyarakat dalam melakukan interaksi. Melalui sistem nilai-nilai itulah, etni yang hidup dan menetap di Panimbang telah menjadikan sebagai masyarakat yang saling mengikatkan diri dalam komunitas yang hidup dengan kemajemukan di Panimbang dengan hidup berdampingan dengan kegiatan sebagai nelayan dan maupun bukan nelayan tetap merasa satu kesatuan serta ikatan yang memiliki kesamaan pekerjaan dan maupun yang tidak memiliki kesamaan pekerjaan. Berdasarkan ungkapan dari informan sebelumnya, lebih dipertegas lagi oleh informan yang lain oleh BHN (61 tahun) asal etnik Jawa yang sudah menetap 30 tahun di pemukiman pesisir Labuan menungkapkan bahwa: 240 Hidup kami secara berdampingan dengan antar etnik-antar etnik lainnya yang ada di Labuan dan Panimbang ini, sebagai nelayan, telah menjadikan kami satu kesatuan sebagai keluarga besar. Walaupun kami ini berbeda asal usul antar etnik bangsa, namun ada nilai-nilai mata pencaharian yang mempersatukan kami yang sebenarnya tidak akan menjadikan kami saling melupakan. Karena dalam melakukan kegiatan melaut, kami memiliki budaya yang sama untuk tetap saling menjaga dan bekerjasama dalam mewujudkan dan mendapatkan penghasilan. Melakukan kegiatan pun kita saling membantu dalam berbagai hal kekuarangan yang kami alami, terkait dengan kelengapan-kelengkapan alat-alat tangkap sebagai nelayan. (wawancara 16 April 2013) Berdasarkan hasil wawancara itu, terungkap bahwa komunitas yang menetap di pesisir Labuan memiliki kesamaan dalam kehidupan untuk tetap saling berdampingan dengan antar etnik-antar etnik lainnya yang ada di Labuan. Tentunya rasa persatuan itu karena adanya kesamaan bermatapencaharian sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan itu pua telah menjadikan komunitas antar etnis itu, menjalin rasa persatuan dan kesatuan sebagai bagian keluarga besar bermatapencaharian sebagai nelayan. Sebenarnya diantara sesama komunita itu, telah menyadari bahwa mereka berasal dari berbeda asal usul antar etnik bangsa, namun ada nilai-nilai mata pencaharian yang mempersatukan mereka dalam internalisasi nilai-nilai budaya kenelayanan. Kerjasama sesama komunitas nelayan juga sebenarnya menjadikan mereka untuk tidak saling melupakan antara satu sama lainnya. Karena dalam melakukan kegiatan melaut, memiliki budaya sebagai pelaut yang sama untuk tetap saling menjaga dan bekerjasama dalam mewujudkan dan mendapatkan penghasilan. Kegiatan melautpun tetap saling membantu dalam berbagai hal kekurangan yang dialami diantara mereka terutama dalam hal kelengapan-kelengkapan alat-alat tangkap sebagai nelayan. Selain budaya kebersamaan dan senasib dalam bermatapencaharian, maka sebagai masyarakat yang memiliki nilai-nilai pergaulan pun tidak terlepas adanya ikatan-ikatan budaya kesantunan. Sebagai bangsa yang besar Indonesia telah memiliki berbagai kelebihan-kelebihan dalam hal berbudaya, demikian pula halnya pada masyarakat yang hidup secara lokal, telah memiliki sikap diantaranya adalah sikap ramah tamah, saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, tolong-menolong dan besarnya rasa toleransi di dalam masyarakat menjadikan masyarakat itu semakin kuat hungungan sosialnya. Pendekatan budaya toleransi, tentunya sangatlah penting dalam kehidupan di lingkungan antar etnis, sebagaimana pula halnya terjadi di Labuan yang telah dialami oleh MHMD (65 th) berasal dari etnis Sunda mengatakan bahwa Selama kami hidup disini dengan bedampingan tiga etnis yang berbeda-beda latar belakang, yakni etnis sunda dianggap sebagai komunitas yang pembawaan cara bahasa dan sikapnya sangat lembut. Demikian pula etnis Jawa yang dianggap masyarakatnya juga tergolong lembut pembawaanya, namun ketika bertemu dengan etins Bugis yang dianggap keras oleh etnis yang lainnya. Akan tetapi setelah kami melakukan hubungan-hubungan yang terkait dengan pergaulan hidup kami, baik secara ekonomi, sosial, keagamaan dan kepercayaan lainnya, tidak pernah mengalami suatu pertentangan dan atau perselisihan diantara kami. Dalam kegiatan ritual-ritual pun kami tetap saling memahami dan saling menghargai, karena kita sama-sama menyadari bahwa sesama manusia kita semua sama dalam mencari penghidupan untuk keluarga. (wawancara 13 April 2013) Faktor Kekerabatan Keberadaan masyarakat ketiga etnis tersebut telah terbina dengan baik, secara turun temurun dan tanpa membeda-bedakan dengan komunitas lainnya. Selain faktor 241 budaya dan nilai-nilai dalam sistem hidupnya, yang mengakibatkan semakin menyatu dalam perbedaan. Pengakuan perbedaan dalam masyarakat pada komunitas antar etnis, merupakan suatu kewajaran karena kehadirannya dari berbagai latar belakang yang berbeda. Faktor berikutnya, yaitu hubungan kekerabatan yang ada diantara mereka. Hal ini merupakan salah satu faktor penting terwujudnya integrasi sosial. Melalui pendekatan kekerabatan tentu tidak lepas kaitannya dengan masalah pernikahan. Faktor kekerabatan merupakan pengelompokan atas sejumlah orang yang masih berhubungan, baik karena keturunan maupun perkawinan yang mencakup identitas dan peranan yang digunakan oleh individu-individu dalam interaksi sosial mereka. Dengan kata lain, sistem kekerabatan terjadi karena keturunan dan perkawinan serta tali darah. Namun dibalik itu sistem kekerabatan secara sosial pun terjadi karena adanya faktor kedekatan yang sangat akrab dan sangat cukup lama melakukan hubungan secara sosial. Kondisi itu, terjadi pula pada komunitas nelayan, setelah mereka memiliki hubungan kedekatan dan pekerjaan yang selama ini dilakukan secara turun temurun melalui kesamaan sistem mata pencaharian. Sistem perkawinan antar etnik dan suku bangsa yang berbeda itu, telah melahirkan tali kekerabatan yang semakin dekat antara masyarakat yang berbeda latar belakang, antar etnik, ras. Fenomena yang terjadi di Panimbang telah terjadi suatu pola perkawinan silang antar etnik. Masyarakat yang melakukan tali perkawinan yang berbeda antar etnik itulah, telah mengalami berbagai perkembangan sisitem kekerabatan dan tali persaudaraan semakin melekat. Perkawinan capuran dengan perbedaan etnik, tidak melahirkan suatu ketegangan antar budaya. Kondisi saling memahami pertemuan dua kutub keluarga antar etnik itu, telah mengarah pada hubungan sosial yang semakin dekat antara komunitas nelayan yang berbeda di perkampungan Panimbang. Komunitas nelayan yang melakukan pernikahan campuran baik antara suku Jawa maupun suku Bugis dan juga dengan suku Sunda tidak selamanya memiliki profesi sebagai nelayan. Namun sebaliknya ada juga profesi sebagai nelayan melakukan perkawinan campuran. Sebagaimana MUH (47 tahun) masyarakat asal antar etnik Jawa melakukan pernikahan campuran dengan antar etnik Bugis, mengatakan bahwa : Melalui pernikahan antar etnis yang saya lakukan, sebenanarnya awalnya membicarakan perbedaan-perbedaan, kebiasaan-kebiasaan masing-masing adat kami. Lama kelamaan dalam perkawinan kami sudah 25 tahun telah berlangsung tidak ada kendala. Dan anak-anak kamipun mengikuti aturan nilai-nilai yang berlaku pada kedua etnis yang melekat dalam keluarga kami. Sebenarnya melalui perkawinan antr etnis yang kami lakukan, malah menambah kumpulan-kumpulan keluarga kami dan jumlahnya semakin besar. Jumlahnya pun semakin bertambah dan kamipun punya keluarga pada dua perkampungan dan dua etnis yang berbeda. Perkawinan kamipun semakin merekatkan perbedaan menjadi suatu kekuatan dalam mempersatukan dua etnis yang berbeda. (Wawancara 16 Mei 2013) Berdasarkan hasil wawancara itu terungkap bahwa pernikahan antar etnis, sebenarnya tahap perkenalan budaya yang paling awal perlu dibicarakan. Mengapa hal itu penting karena adanya perbedaan-perbedaan kebiasaan-kebiasaan masing-masing komunitas yang berbeda latar belakang. Perbedaan yang dipersatukan dalam wadah yang sama melalui tali perkawinan, lama kelamaan akan berlangsung tidak ada kendala. Kedua keluarga yang melakukan perkawinan campuran etnis mengikuti aturan nilai-nilai yang berlaku pada kedua etnis yang melekat dalam keluarganya. Melalui tali perkawinan antar etnis akan menambah kumpulan-kumpulan keluarga mereka dan jumlahnya semakin besar. Keluarga yang melakukan perkawinan campuran semakin merekatkan perbedaan menjadi suatu kekuatan dalam mempersatukan dua etnis yang berbeda. 242 Dengan demikian dapat diketahui bahwa hubungan kekerabatan yang terjadi akibat adanya perkawinan diantara masyarakat asli dan pendatang yang berbeda antar etnik bangsa, menyebabkan terjadinya proses interaksi yang semakin meluas di antara kedua pasangan dan pihak-pihak keluarganya. Hal itu, terjadi pula pada komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda bahwa hubungan kekerabatan diantara mereka yang sudah melakukan perkawinan campuran. Namun dalam pernikahan yang berasal dari keluarga yang berbeda biasanya kedua pasangan yang masih baru mereka tinggal dan menetap pada kedua orang tunya. Mereka memilih kebanyakan menetap dilingkungan orang tua dan tidak memutuskan tali silahturahmi dengan orang tua mereka. Jadi perkawinan bukan mengurangi jumlah keluarga, namun semakin memperkuat keluarga lebih luas dan terintegrasi dengan baik lagi. Dalam kenyataannya, perbedaan budaya dan latar belakang asal usul daerah tidak menjadi persoalan bagi hubungan sosial kemasyarakatan di Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda sebab masyarakat menganggap bahwa perkawinan semacam itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat yang majemuk. Hal ini juga didorong faktor kerukunan hidup antar etnik yang relatif tinggi dan tidak ditemuinya sikap fanatisme berlebihan dalam kehidupan kesehariannya. Kondisi perbedaan itu pun meyakini tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan baik dipermukaan maupun dalam hati secara individu maupun kolektif di perkampungan Binuangen. Kekerabatan dibangun bisa melalui tali pernikahan maupun dengan hubungan kait mengkait dalam satu bingkai tali rumpun keluarga. Kekerabatan secara sosial pun juga terbagung karena faktor kedekatan antara satu etnik dengan etnik lainnya secara terintegrasi. Memelihara kebersamaan satu wadah di perkampungan Panimbang sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan sosial terbangun pula karena adanya kesamaan nasib dan profesi yang sama sebagai nelayan dan kegiatan yang lainnya. Menyatukan masyarakat melalui tali kekerabatan sebenarnya bisa terbangun melalui tali darah atau perkawinan dan bisa terbangun pula melalui hubungan sosial yang tidak memiliki jarak dan antara dalam melakukan hubungan sosial. Bentuk Solidaritas Sosial Perkawinan Campur Melalui perkawinan campur yang terjadi di masyarakat Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan sunda sebenarnya merupakan hal yang sudah lumrah di Labuan dan Panimbang. Perkawinan dapat terjadi melalui asal muasalnya saling mencintai. Dan perkawinan yang terjadi antar etnis di Labuan maupun Panimbang sebenarnya sangat sedikit dan bahkan tidak pernah terjadi pernikahan dengan perjodohan secara paksa. Pendekatan perkawinan sebenarnya seringkali didapati di dalam masyarakat baik antara yang berbeda etnis. Perkawinan campuran dapat dijadikan sebagai wadah untuk merekatkan masyarakat di Panimbang maupun Labuan. Perkawinan campur atau sering disebut perkawinan silang, merupakan ikatan karena adanya jodoh dan perasaan saling suka. Munculnya perasaan suka sama suka itulah, membuat mereka melangsungkan perkawinan dan tanpa melihat latar belakang asal usul dan etnik. Melangsungkan perkawinan campuran di perkampungan Labuan maupun Panimbang hampir tidak menemukan kendala, karena komunitas yang berdiam di wilayah tersebut sudah terjalin cukup lama dan juga dari aspek kebiasaan-kebiasaan dalam proses 243 kegiatan prosesi tidak pernah menjadi kendala, karena sejak dilakuakan proses pertunangan sudah dibicarakan. Nilai-nilai Sosial Dalam implementasi nilai-nilai sosial, tentunya seiap etnis memiliki komitmen dan bertumpu pada nilai-nilai sosial yang dimiliki dan di yakininya sebagai pegangan dan pedoman untuk mencapai kesuksesan. Hal itu sebagaimana di tuturkan oleh Asep Haryadi (34 tahun) berasal dari suku sunda bahwa : Berbicara tentang nilai-nilai kepercayaan merupakan salah satu modal solidaritas, pada implementasinya yang dianggap paling mudah dilakukan oleh siapapun, karena hanya dalam bentuk kontrak sosial yang sangta sederhana. Komunitas nelayan di Panimbang justru melihat sebagai modal yang paling utama dalam memperkuat tali kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan sebagai nelayan. Faktor utama yang mendukung jalannya nilai-nilai kepercayaan adalah saling mendudukkan sesorang pada posisinya secara sosial dan tanpa memandang status sosial ekonominya maupun asal muasal etnisnya. Berdasarkan hasil wawancara itu terungkap bahwa kepercayaan sesorang tercermin dalam nilai-nilai sebagai pegangan untuk menjadi modal solidaritas. Kepercayaan bagai kalangan masyarakat di perkampungan Binuangen dalam implementasinya tidak terlalu berat dan bahkan dianggap paling mudah untuk dilakukan pada kalangan internal siapapun. Mengapa hal itu dianggap mudah untuk dilakukan, karena hanya dalam bentuk kontrak sosial yang sangta sederhana. Namun dalam perkembangan saat ini masyarakat antar etnis melihat bahwa dengan adanya nilai-nilai yang mengatur secara sosial menjunjung tinggi nilai- dan pranata sosial sebagai modal yang paling utama dalam memperkuat tali kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan sebagai nelayan. Faktor utama yang mendukung jalannya nilai-nilai kepercayaan adalah saling mendudukkan sesorang pada posisinya secara sosial dan tanpa memandang latar elakang dan asal usul individu maupu kemasyarakatan. Internalisasi tekait nilai-nilai kepercayaan ditumbuhkan melalui sikap dan prinsipprinsip rendah hati, tulus dari dalam diri untuk dapat saling menerima antar suku yang satu dengan suku lainnya. Sebagai masyarakat yang multikultural yang berdiam di perkampungan Panimbang menyadari suatu nilai-nilai saling mencintai perbedaan. Walaupun mereka saling menyadari bahwa perbedaan yang selama ini terjadi memang kadangkala sangat mencolok dari segi kepemilikan teknologi alat tangkap dan eos kerja yang dimiliki oleh nelayan. Misalnya Suku Bugis dianggap lebih ulet dalam bekerja, sehingga kepemilikan berbagai fasilitas daya dukung kehidupannya lebih maju dan lebih berkembang dibandingkan dengan suku lainnya. Keuletan bekerja keras sebanarnya sudah merupakan salah satu prinsip bagi setiap individu untuk menciptakan kolektivitas, dan termasuk pada komunitas nelayan yang bermukim di perkampungan Panimbang. Etos kerja berisi tentang nilai-nilai semangat dan keinginan untuk mengubah pola hidup seseorang. Pertukaran nilai tentang pengalaman dalam melakukan aktifitas sebagai nelayan. Sebenarnya, hampir semua masyarakat memiliki nilai-nilai kolektivitas dalam menjunjung nilai-nilai semangat untuk bekerja, namun yang jadi persoalan adalah pengalaman yang berbeda-beda dalam menggapai impian dan kenyataan hidup. Sebagai komunitas nelayan di Panimbang nilai-nilai etos kerja seringkali dilakukan pada kesempatan yang tidak terstruktur dengan berkumpul secara berbarengan walaupun sifatnya temporer dan membicarakan tentang pengalamanpengalaman hidup mereka dan termasuk dalam melakukan aktifitas sebagai nelayan. Nilai-nilai dan pranata-pranata sosial yang memperkuat internal masyarakat jawa sebenarnya ada komitmen tersendiri dalam menujukkan eksistensi dirinya, namun sebagai 244 manusia yang bersosialisasi manusia sebenarnya tidak boleh membanggakan dirinya, sebagaimana Wahono (41 tahun) suku jawa menuturkan bahwa: Kami sebagai masyarakat Jawa Memiliki nilai sosial yang kami pegang dalam berbagi pengalaman sebenarnya bukan sebagai ajang membanggakan diri mereka, namun hanya sekedar untuk mempererat tali solidaritas dan kesetiakawanan sebagai sesama nelayan yang menginginkan kemajuan bersama. Sebagai komunitas nelayan, tentu memiliki berbagai perbedaan pengalaman dan setiap etnis memiliki nilai-nilai yang dijunjung dalam meningkatkan etos kerja, berupa semangat yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga maupun timbul dan tumbuh dilingkungan sosial masyarakat. Nilai-nilai sosial untuk pemenuhan keperluan sebagai komunitas nelayan sangat diperlukan, misalanya bagi etnis jawa mengenal nilai-nilai semangat etos kerja dengan prinsip maju untuk berhasil yang dipegang sebagai penyemangat untuk mempersatukan sesama komunitas nelayan. Berdasarkan hasil wawancara itu, terungkap bahwa kalangan masyarakat Jawa Memiliki nilai sosial yang selama ini yang dianut dalam berbagi pengalaman masingmasing yang membedakan dengan suku lainnya. Namun nilai-nilai yang diyakini sebagai etos kerja sebenarnya bukan sebagai ajang membanggakan diri mereka, namun hanya sekedar untuk mempererat tali solidaritas dan kesetiakawanan sebagai sesama nelayan yang menginginkan kemajuan bersama. Sebagai komunitas nelayan, tentu memiliki berbagai perbedaan pengalaman dan setiap etnis memiliki nilai-nilai yang dijunjung dalam meningkatkan etos kerja, berupa semangat yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga maupun timbul dan tumbuh dilingkungan sosial masyarakat. Nilai-nilai sosial untuk pemenuhan keperluan sebagai komunitas nelayan sangat diperlukan, misalanya bagi etnis jawa mengenal nilai-nilai semangat etos kerja dengan prinsip maju untuk berhasil yang dipegang sebagai penyemangat untuk mempersatukan sesama komunitas nelayan. Nilai-nilai sosial sebagai pranata, sebenarnya berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan sesama nasib dan kesamaan profesi sebagai nelayan dalam memenuhi keperluan dalam melakukan aktifitas ke laut. Kehdupan dalam kebersamaan dengan melakukan kegiatan tolong menolong dalam pergaulan melalui nilai-nilai kepercayaan dan sopan santun merupakan bentuk implementasi nilai-nilai pergaulan yang mengedepankan kekerabatan sebagai sistem berbagi pengalaman. Kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam kegiatan melaut, akan mengalami keringanan apabila dilakukan dengan pendekatan budaya kebersamaan. Sistem kepercayaan dan ritual Komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda memiliki kebiasaankebiasaan dalam meminta restu sebelum melaut. Tujuan dari kegiatan itu, lebih mengarahkan pada pendekatan untuk meminta keselamatan dari sang pencipta. Pentingnya memohon petunjuk dan ridho dari sang pencipta merupakan suatu hal yang sangat wajib sebelum dilakukan penangkapan, agar memperoleh keselamatan dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan melaut. Melalui pendekatan kepercayaan itulah, komunitas nelayan memiliki ikatan-ikatan yang sama dalam memohon ridho dan pendekatan kepada sang pencipta. Melalui ritual sesajen dengan membawa makanan ke pinggir laut, yang berisi didalamnya nasi 3 rupa, beras warna merah, putih dan hitam menandakan sebagai pendekatan meminta untuk dilindungi dari berbagai segi penjuru. Selain nasi sebagai sumber penghidupan dan juga lauk pauk berupa ayam sebagai bentuk simbol mendapatkan rahmat dan bertambah rezeki. Melalui nilai-nilai kebiasaan secara turun temurun itulah, komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda merasa memiliki kedekatan dalam 245 hal ritual tersebut. Kebersamaan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya integrasi dari nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda. Komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda yang menetap di pesisir Panimbang sebagai masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, sehingga keakraban juga terbangun dalam kegiatan keagamaan dan ritual-ritual dalam hal kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan. Kegiatan silaturahmi juga terlihat dalam kegiatan shalat lima waktu maupun shalat Jumat. Pelaksanaan kegiatan shalat Jumat dan masyarakat antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda semuanya berbaur di dalamnya. Suasana keakraban pun terlihat dengan jelas, bahwa melalui pendekatan acara keagamaan memberikan nuansa kesejukan bagi masyarakat yang memeluk agama yang sama. Selain itu pada kegiatan hari raya keagamaan pun dapat menjadi momentum yang sangat tepat untuk bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya, tanpa melihat latar belakang antar etnik. Kunjungan silaturahmi kepada teman, keluarga dekat, dan tetangga, merupakan hal yang lumrah bagi komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda, apalagi dalam rangka hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hubungan sosial keagamaan antara penduduk setempat dengan warga pendatang menjadikan warga Komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda lebih terbuka untuk menerima berbagai pengaruh budaya luar diantara mereka. Berdasarkan informasi dari beberapa informan mengungkapkan bahwa kegiatan hari raya sebagai momentum untuk saling melebur diri menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Wadah kegiatan ritual keagamaan merupakan momentum untuk saling memaafkan satu sama lainnya. terjadi pada komunitas merekapun tetap menjadi kehangatan yang sangat baik. Keberadaan hari-hari besar diantara mereka merupakan momentum untuk lebih menambah keakraban di antara mereka. Kegiatan silaturahmi keagamaan hanya berlangsung sebanyak dua kali setahun yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha komunitas nelayan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda yang jarang ketemu dengan berbagai kesibukan masing-masing setidaknya memiliki dua kali pertemuan yang pasti dilakukan oleh mereka yaitu pada hari-hari besar tersebut. Walaupun kegiatan tersebut merupakan hubungan individual diantara mereka untuk saling bersilahturahmi, namun setelah diarahkan bagian dari ritual keagamaan, maka mereka menyadari bahwa betapa pentingnya saling hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut. Perayaan saling silaturahmi dalam keyakinan baik melalui pendekatan keagamaan maupun upacara-upacara ritual lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenelayananan. Pada kegiatan hari raya idul fitri merupakan salah satu pendekatan yang selama ini sangat bagus dilakukan untuk saling mengunjungi baik sesama etnis maupun lintas etnis. Berdasarkan penuturan beberapa informan bahwa kegiatan rutinitas silaturahmi idul fitri merupakan ajang tahunan yan dilakukan dalam pendekatan Halal Bi halal sebagai wadah untuk mengakrabkan kembali yang mungkin selama sebelas bulan tidak terlalu erat karena adanya kesalahan yang dilakukan. Ajang silaturahmi memaafkan dalam hari raya lebaran idul fitri itu, seakan-akan mengajak masyarakat sekitar perkampungan Binuangen untuk saling memaafkan. Walaupun sebenarnya tidak diformalkan namun ajang memaafkan ini di jadikan sebagai momentum untuk memperkuat tali kekeluargaan yang mungkin sempat terputus. Ajang halal bi halal sebagai rangkaian acara untuk mempertemukan masyarakat, dan juga sekaligus mengundang pemerintah setempat RT dan RW, serta tokoh masyarakat berbagai etnis, pemuka agama. Kegiatan halal bi halal ini biasanya dilakukan di masjid dan atau di sekolahan. Melalui kegiatan ajang idul fitri ini, masyarakat saling meningkatkan kerukunan beragama diantara mereka dan menjalin keharmonisan antara masyarakat dan aparaturnya, sehingga mendukung dan mendorong masyarakat untuk saling berintegrasi sesamanya. 246 Selain acara halal bihalal sebagai ajang tahunan, bagi komunitas nelayan di perkampungan Panimbang, memiliki tradisi pula dalam menggelar upacara hari turunnya melaut. Hari turun melaut ini merupakan tradisi tahunan pula yang dilakukan sebagai penanda akan dimulainya melaut. Kegiatan rutinitas hari pertama melaut ini dilakukan dengan pemberian sesajen dalam bentuk makanan atau kegiatan makan bersama yang dilakukan diatas perahu. Biasanya dilakukan pada saat mau berangkat, maka pemilik perahu menyiapkan terlebih dahulu makanan dan mengajak masyarakat atau nelayan yang ada isekitarnya. Tradisi makan bersama diatas perahu pada hari melaut ini, sebenarnya tidak dilakukan semua oleh nelayan dalam bentuk pesta besar-besaran, namun ada orang yang membesar-besarkan. Kegiatan Perekonomian Bentuk kegiatan usaha penangkapan ikan di Labuan maupun di Panimbang dikategorikan sebagai usaha perikanan yang berskala kecil. Bagi komunitas yang berprofesi sebagai nelayan yang, dilakukan secara turun temurun dan pekerjaan sebagai nelayan ditekuni sebagai sumber mata pencaharian keluarganya. Beraktifitas ebagai nelayan merupakan pekerjaan satu-satunya sebagai sumber penghasilan keluarga. Sebagai nelayan merupakan pilihan bagi Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda yang meranau dari kampung halamannya, dan diperoleh dari orang tuanya. Sebelum merantau Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda sudah memiliki keahlian tersendiri sebagai nelayan. Sebagai nelayan yang berskala kecil, kegiatan penangkapan dapat dilakukan sepanjang tahun dan sangat bergantung dari musim. Ketergantungan pada musim itulah akan berdampak pada penentuan daerah penangkapan (fishing ground) yang menjadi sasaran penangkapan. Ketergantungan pada musim itulah, nelayan sering memperoleh pengasilan pasang surut. Apabila musim lagi banyak ikan maka nelayan dapat memperoleh penghasilan lebih banyak. Dan sebaliknya apabila lagi musim paceklik maka hasilnya pun diperoleh dengan apa adanya dan bahkan biaya operasional pun tidak tertutupi. Sebagaimana MHN (50 tahun) bahwa : Saya dan teman-teman yang berdomisili di Kampung Labuan dan juga terjadi di Binuangen memiliki ketergantungan sangat tinggi pada musim, karena perahu yang kami miliki tidak mampu menembus sejauh mungkin, karena keterbatasan ukuran perahu yang kami miliki. Melalui keterbatasn itulah, mengakibatkan kami lebih banyak melakukan penangkapan di sekitar selat sunda saja. Perahu yang saya miliki sama saja teman-teman nelayan lainnya yang berdomisili di pesisir Labuan. Penghasilan yang diperoleh sebenarnya kadang banyak dan kadangkala juga apa adanya, sehingga biaya hidup juga kadang tertutupi dan kadang juga tidak tertutupi. Berdasarkan hasil wawancara itu terungkap bahwa kegiatan ekonomi yang berdomisili di Kampung Labuan memiliki ketergantungan sangat tinggi pada musim dalam menjalankan roda perekonomiannya. Keterbatasan kekuatan dan muatan perahu yang mereka miliki, tidak mampu menembus sejauh mungkin hingga kelaut yang paling dalam, karena selain kekuatan juga memiliki keterbatasan ukuran perahu yang mereka miliki. Melalui keterbatasan itulah, mengakibatkan nelayan lebih banyak melakukan penangkapan di sekitar Selat Sunda saja. Perahu yang dimiliki oleh nelayan lainnya hamir merata yang berdomisili di pesisir Labuan. Demikian pula halnya dengan penghasilan yang diperoleh sebenarnya kadang banyak dan kadangkala juga apa adanya, sehingga biaya hidup juga kadang tertutupi dan kadang juga tidak tertutupi. Daerah penangkapan ikan di Kecamatan Labuan adalah Selat Sunda, Selatan Jawa/Samudera hindia dan Laut Jawa. Berdasarkan wawancara dengan nelayan daerah 247 penangkapan yaitu sekitar Selat Sunda, Tanjung Panaitan, Kepulauan seribu, Kerakatau, Rompang, Sumur, Kelapa Koneng, Pulau Pucang, Kalianda, Cemara, Karang bawah dan Batu Item. Daerah penangkapan ini ditempuh para nelayan sekitar 3-4 jam perjalanan. Penentuan daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di Kecamatan Labuan dan Panimbang umumnya masih berpedoman pada faktor-faktor alam. Nelayan masih menggunakan pengetahuan sederhana seperti adanya burung yang terbang di atas perairan atau riak di air yang menandakan adanya ikan. Dengan hanya mengandalkan sebatas pengetahuan tradisional ini maka nelayan yang beroperasi menangkap ikan berada pada keadaan berburu atau pergi dengan tujuan mencari yang tidak pasti letaknya. Akan tetapi karena tingkah laku ikan yang sudah diketahui nelayan yaitu dimana ikan memijah dan dimana ikan biasa berkelompok mencari makan maka hal ini dapat digunakan nelayan dalam menentukan posisi ikan. Keberadaan kelompok ikan juga juga dapat diketahui dengan melihat permukaan laut yang berbuih, adanya ikan-ikan yang melompat-melompat di permukaan atau burung yang menukik dan menyambar ke permukaan laut. Selain itu, penentuan daerah penangkapan juga ditentukan berdasarkan pengalaman dan informasi dari kapal yang baru mendarat. Hubungan bermasyarakat pada Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda terlihat dalam aneka kegiatan perekonomian yang tidak dibatasi oleh perbedaan antar etnik, agama dan budaya. Ini terlihat dari interaksi masyarakat ketika berada di pasar Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda sebagai pusat kegiatan perekonomian warga yang menetap di Labuan mapun Panimbang. Pasar Labuan yang berbatasan secara langsung dengan tempat pendaratan perahu, langsung dijual hasilnya ke pasar. Hasil tangkapan ada yang dijual di tingkat lokal dipasar Labuan dan adapula yang di bawa keluar misalnya kepasar Pandeglang dan bahkan ada yang dipasarkan sampai ke Jakarta. Aktivitas dipelelangan pun didominasi oleh masyarakat antar etnis yang menetap disekitar Labuan. Proses integrasi masyarakat lewat kegiatan perekonomian juga ditandai oleh adanya koperasi serba usaha yang anggotanya terdiri dari komunitas nelayan yang diberi nama koperasi sumber usaha yang dibangun secara bersama-sama oleh nelayan antar etnis di Labuan. Secara umum Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda memiliki koperasi atau kegiatan ekonomi yang berfungsi sama seperti koperasi dengan kepengurusan yang tidak membedakan antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda. Kegiatan ini mengikat masyarakat Komunitas antar etnis Bugis, Jawa dan Sunda menjadi satu kesatuan tanpa diskriminasi etnis manapun juga. Melalui wadah simpan pinjam terkait operasional selama melaut dapat diperoleh dikoperasi dan pada akhirnya mereka saling mengenal satu sama lainnya tentang kebutuhan yang diinginkan dan bahkan tidak sedikitpula melakukan perbincangan tentang melaut. Pada kegiatan kenelayanan nelayan memiliki waktu-wakt tertentu yang dianggap sebagai masa masuknya waktu penangkapan. Waktu penangkapan itu sebenaranya dimulai secara bersama-sama sebagai bentuk kekompakan dalam melakukan operasional di lautan. Kekompakan yang dibangun dalam waktu penangkapan itu, sebenarnya tidak ada aturan yang tertulis, namun lebih mengedapankan pada nilai-nilai kesepahaman agar tercipta harmonisasi antara sesama komunitas nelayan. Berdasarkan penuturan beberapa informan mengungkapkan bahwa sebenarnya waktu penangkapan tidak ada pembatasan, namun hanya lebih pada adanya upacara memperingati hari massal memulai penangkapan. Kesepakatan dan kesepahaman dalam kegiatan ekonomi yang diatur oleh kebiasaan tidak melahirkan suatu pertentangan diantara komunitas nelayan antar etnis di pemukiman Panimbang. Kesadaran kolektif sebagai masyarakat yang tergolog sederhana, komunitas nelayan memiliki elit-elit sentral yang mengatur jalannya sumber ekonomi terutama dalam hal hari baik pertama penangkapan. Penentuan hari baik penangkapan ini 248 dilakukan setelah terjadinya kondisi istirahat panjang yaitu terutama pada pasca atau sesudah berlalunya musim penghujan pada bulan oktober hingga bulan Maret. Selain kegiatan ekonomi proses penangkapan, pada komunitas nelayan juga terjadi hubungan interaksi yang sangat intensitasnya tinggi di lokasi pemasaran. Perkampungan nelayan di Panimbang terdapat lokasi pemasaran baik di pelelangan ikan maupun di pasar tradisional yang berada di sekitar perkampungan Panimbang. Aktifitas ekonomi dalam hal pemasaran, ditemukan dilapangan bahwa ada kelompok-kelompok pemasar hasil tangkapan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan selama ini bagi komunitas nelayan. Secara struktural komunitas nelayan ada yang memasarkan hasil tangkapannya dengan menjual langsung ke pasar dan ada pula yang memasarkan di pelelangan secara langsung dan di jual secara terbuka. Kelompok nelayan seperti ini yang berdasarkan informasi adalah kelompok pemilik perahu dan alat tangkap sendiri. Kelompok pemilik perahu dan alat tangkap, biasanya tidak tergantung pada pemilik modal atau kelompok pengumpul sehingga bisa dipasarkan secara langsung baik di pasar lokal maupun di pelelangan. Lain halnya pada komunitas nelayan yang sangat menggantungkan modal dari pihak ketiga. Misalnya Asep nelayan sunda yang bergantung modal pada Pak udin etnis Bugis yang memberikan bantuan permodalan pada Asep sebelum berangkat melaut. Asep sebagai komunitas nelayan hanya memiliki perahu dan tidak memiliki alat tangkap yang memadai serta bekal untuk melaut, sehingga memaksa dirinya untuk mencari gantungan permodalan. Bagi Asep ketergantungan pada pemilik modal atau yang membantu selama ini, walaupun berbeda etnis, namun tidak keberatan, karena melakukan gantungan pada siapapun aturan mainnya sama. Dari segi aspek pemasaran Asep merasa memiliki kenyamanan bekerjasama dengan pak udin, karena aspek pemasaran tidak harus diatur dan dikondisikan oleh Pak Udin. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan dari beberapa informan mengungkapkan bahwa yang lazimnya atau kebiasaannya kalau ada nelayan yang menggantungkan aspek permodalan pada seseorang maka biasanya akan mengarahkan dan mengatur dari segi aspek pemasaran. Pada kasus Asep sebenarnya bisa saja juga berlaku, kalau tidak memiliki perahu sebagai modal awal yang mendukung sebagai sarana alat tangkap. Aspek kegiatan perekonomian dalam hal operasional penangkapan, bukan hanya dilihat dari kesamaan suku untuk menggantungkan diri dalam hal permodalan, namun keberadaan etnis pun sangat tertib dan toleransinya sangat tinggi. Dalam hal kegiatan siklus ekonomi yang berjalan selama ini tidak pernah mengganggu aktivitas karena adanya perbedaan suku. Kesamaan karaktersistik dan menjadi masyarakat lokal, bagi komunitas nelayan bekerja bersama-sama sudah menjadi bagian dari hal penting untuk dilakukan dan diwujudkan. Hidup berdampingan dengan lain suku dibutuhkan toleransi agar hidup lebih seirama. Kesimpulan Karasteristik komunitas nelayan antar etnik memiliki kesamaan dalam hal wilayah pemukiman, pola hidup dan juga dalam hal tradisi sebagai komunitas nelayan terutama dalam hal melakukan aktifitas menangkap ikan di laut. Untuk proses sosial terjadi adaptasi melalui pendekatan budaya dengan saling memahami serta tumbuh saling pengertian dalam menghargai nilai-nilai yang masing-masing telah diyakininya. Selain itu, faktor kekerabatan terjadi selama ini melalui hubungan kedekatan berdasarkan pada pola pemukiman dan aktifitas yang sama. Perkawinan antar etnik, selama ini terjadi dan menjadi media untuk saling memahami dan terjadi pembauran satu etnik dengan etnik yang lainnya. 6. DAFTAR PUSTAKA 249 Abraham, Francis. 1991. Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teor Umum Pembangunan. Yogyakarta: Tiara Wacana. Amiruddin, Suwaib. 2013 Pembangunan Masyarakat partisipatif, Serang: Getok Tular BPPT-Wanhankamnas, 1996. Konvensi Benua Maritim Indonesia. BPPT-Hanhankamnas: Jakarta. Brannen, Julia. 1997. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Jakarta: Pustaka Pelajar. Creswell, J. W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SagePublications. Daniel, Lehner. 1980. Kebudayaan Masyarakat Tradisional, Yogyakarta: Gadjahmada University Press. Durkheim. Emile. 1964. The Devision of Labor in Society. Terjemahan George Simpson New Work. The Free Press. Eder, Klaus. 1992. Contradictions and Social evolution: A Theory of The Social Evolution and Modernity. dalam H. Haferkamp and N. J. Smelser (Eds), Social Change and Modernity. California: University of California Press. Eisentadt, S.N. dan L. Roniger. 1984. Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Canbridge: Canbridge University Press. Eyerman, Ron. 1992. Modernity and Social Movements. dalam H. Haferkamp and N. J. Smelser (Eds), Social Change and Modernity. California: University of California Press. Garna K.Iudistira. S. 1984. Sosiologi Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta. .1993. Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan masa Depan di Nusantara, Bandung: Pascasarjana Unpad. Habennas, Jurgen. 1983. Modernity: An Incomplete Project, dalam H. Foster (Ed.), Postmaderri Culture. London: Pluto. Haferkamp, H. dan N.J Smelser (Eds.). 1992. Social Change and Modernity. California: California University Press. Johnson, Paul. Doyle. 1990. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I dan II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Koentjaraningrat, 1982. Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta; LP3ES. Kusnadi. 2005. Strategi hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta ; LKis Lauer H. Robert, 1993, Prespectives on Social Change (terjemah, Alimandan S.U) Prespektif Tentang Perubahan Sosial, Rineneke Cipta, Jakarta. Maliowski. Bromslaw. K. 1945. A Scientific Theory of Culture and other Essay, New York: Oxford University. Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya. Parsons, Talcott. 1951. The Social System. New York: The Macmillam Company. Pelly, Usman, 1994, Area dengan Perahu Bugisnya: sebuah Studi Mengenai Pewarisan Keahlian Orang Ara Kepada Anak dan Keturunannya; Ujungpandang, PLPIIS. Pelras, Cristian. 1984, Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Bugis Makassar,Ujungpandang, PLPIIS-YIIS. Satria, Arif. 2002. Sosiologi Masyarakat Pesisir . Jakarta : Pustaka Cidesindo Suwitha, I.P.G. 1991. "Teknologi, Pola Pikir dan Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Pancana", dalam Mukhlis (Ed.), Teknologi dan Perubahan Sosial Di Kawasan 250 Pantai. Ujung Pandang: P3MP-Unhas. BAB II GERAKAN AGRARIA 251 PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN MEDIASI (Kasus Petani Desa Rengas dan Limbang Jaya dengan PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera Selatan) 1 Alfitri, 2Firman Muntaqo, 3Raniasa Putra 4Rogaiyah, 5Abdul Kholek Guru Besar Sosiologi Pembangunan FISIP Universitas Sriwijaya, email [email protected] 2 Dosen Hukum Agraria, Ketua Prodi Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, [email protected], 3 Dosen Kebijakan Publik, Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya , 4Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya, 5 Labsosio, Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji akar, dinamika, dan penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat petani Rengas dan Limbang Jaya dengan PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, pendalaman data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan Focus Group Discusion (FGD).Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik yaitu perbedaan landasan klaim, mekanisme ganti rugi tidak transparan, penyerobotan lahan oleh perusahaan. Temuan penting, bahwa konflik petani desa Rengas dengan PTPN VII Cinta Manis, berujung pada tindakan reklaiming oleh petani, dianggap sebagai kemenangan perlawanan petani dalam konflik, sehingga menarik lebih banyak wilayah yang masuk kedalam kontestasi konflik diantaranya petani desa Limbang Jaya. Kedua kasus tersebut memiliki tipikal konflik yang berbeda,dikarenakan konflik masyarakat desa Rengas memiliki basis historis perlawanan sejak awal, sedangkan konflik masyarakat desa Limbang Jaya sebagai eskalasi dari konflik desa Rengas. Penyelesain konflik ditempuh 252 melalui jalur advokasi oleh unsur masyarakat sipil, dan jalur mediasi olehpara pemangku kepentingan.Kedua pendekatan penyelesaian tersebut belum mampu memberikan penyelesaian yang berkelanjutan, dikarenakan upaya advokasi cenderung konfrontasi yang masif, sedangkancara mediasi dilakukan hanya sebatas prosedural yang belum menyentuh tataran substantif. Kata Kunci : Konflik, Dinamika, Mediasi. Abstract This paper aims to examine the roots, dynamics, and resolution of land disputes between farming communities and Limbang Jaya Rengas with PTPN VII Cinta Manis in Ogan Ilir, South Sumatra. The method used is the method of qualitative deepening of the data is done by in-depth interviews, observation and Focus Group Discussion (FGD). The results showed that the root of the conflict is the cornerstone differences claims, compensation mechanisms are not transparent, annexation of land by companies. The finding is important, that the conflict Rengas village farmers with PTPN VII Cinta Manis, leads to action reklaiming by farmers, farmer resistance is regarded as a victory in the conflict, thus attracting more areas coming into conflict contestation among Limbang Jaya village farmers. Both cases have different typical conflict, because conflict Rengas rural communities have a history of resistance since the beginning, while the conflict Limbang Jaya village communities as an escalation of the conflict Rengas village. A settlement of conflict through such advocacy by civil society elements, and channels of mediation by stakeholders. Both approaches completion has not been able to provide a sustainable settlement, due to advocacy efforts tend confrontation: the massive, whereas how mediation is done merely procedural has not touched the substantive level. Keywords: Conflict, Dynamics, 1. PENDAHULUAN Eskalasi konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun terakhirtergolong tinggi.Berdasarkan data Walhi Sum-Sel tercatat sebanyak 56 kasus konflik lahan yang di advokasi tahun 2010-2014(Walhi, 2014).Karakteristik konflik lahan tersebut mencakup dua kategori yaitu masyarakatdengan perusahaan milik negara danmasyarakat dengan perusahaan swasta. Konflik yang terjadi selalu diiringi tindakandestruktif, bentrok fisik, penjarahan, dan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Catatan Komnas HAM konflik lahan di Sumatera Selatan, selalu diikuti oleh tindak kekerasan mengakibatkan makin tingginya potensi pelanggaran HAM dalam konflik tersebut (Sumeks, 2012). Temuan Abdul Kholek (2011) dalam mengkaji dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat petani versus PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, ada indikasi pengulangan konflik lahan yang berujung tindak kekerasan, diakibatkan tidak adanya penyelesaian yang komprehensif dilakukan oleh pihak terkait. Siklus konflik yang terjadi ketika memuncak dan lahirnya kekerasan, hanya ditanggapi secara insidental oleh pemerintah, hanya formalitas, dan akhirnya terjadi pembiaran. Kondisi inilah mengakibatkan konflik menjadi semakin masif dan kasus konflik meningkat cukup signifikan. 2. TINJAUAN PUSTAKA Kajian tentang konflik telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Kim (2011) menjelaskan bahwa pengembangan lahan perkotaan di Vietnam telah menjadi sumber konflik sosial baru, bagi mereka yang direlokasi telah meningkatkan daya tawar dan menerima paket kompensasi lebih baik. Penelitian lain dilakukan oleh Coombes (2012) 253 yang menyimpulkan bahwa masyarakat adat hidup dalam lingkungan yang menantang dan terlibat dalam negoisiasi yang kompleks, sehingga ditemukan prinsip lingkungan sosio kultural dalam penyelesaian konflik. Pada sisi partisipasi dalam penyelesaian konflik dibahas oleh Gloper (2008) dalam penelitiannya tentang pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam menentukan perencanaan kepemilikian lahan, sehingga diperlukan pengambilan kebijakan tentang lahan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat (Pratap, 2010). Sebagai perbandingan hasil penelitian Cain (2010) di Angolamenemukan pendekatan aprtisipatif untuk pengolahan lahan menjadi projek percontohan terutama bagi pemerintah dengan tujuan mempengaruhi program nasional yang baru untuk perumahan dan pemukiman di perkotaan. Temuan penelitian yang dilakukan di beberapa negara menekankan perlakuan masyarakat yang lebih diutamakan dalam upaya meredam dan mengendalikan konflik, namun pendekatan mediasi untuk menyelesaikan konflik dapat menjadi salah satu alternatif. Menurut Barsky (2000), penyelesaian konflik dapat lebih efektif dengan menggunakan model mediasi antar kelompok dan proses terkait. Konflikantar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan nilai inisial ,keyakinan, konflik seperti itu sering dipersulit oleh stereotip, prasangka, mis-komunikasi, dan bentuk kesalah pahaman.Model untuk menangani konflikantar kelompok melalui debat, dialog, pemecahan masalah, danintervensi berbasisi dentitas. Sejalan dengan Alfitri dkk (2014), bahwa kelembagaan non formal berupa hukum adat yang dipraktekkan melalui pengadilan adat, dengan prinsip mengedepankan ruang dialogis, penyampaian pendapat secara seimbang tanpa tekanan, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, telah mampu memberikan ruang damai dan harmonis secara berkelanjutan bagi masyarakat adat di Sumatera Selatan. Terkait metode penyelesaian konflik pertanahan,tentunya diperlukandukungan basis data yang komprehensif dan detail dari berbagai perspektif, baik dari masyarakat, perusahaan atau pemerintah. Menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengkaji secara komprehensif akar konflik, dinamika, dan penyelesaian konflik lahan, sebagai dasar rumusan kebijakan bagi pemangku kepentingan. 3. METODE PENELITIAN Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan data akan lebih dalam digali dan dipahami dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Penggalian data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terpokus, observasi. Data primer dan data sekunder, akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan utama penelitian. Konflik yang dikaji yaitu petani desa Rengas dan desa Limbang Jaya dengan PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Alasan dipilihnya kedua lokasi tersebut dikarenakan kedua lokasi konflik memiliki akar yang sama tetapi rentang waktu konflik yang berbeda,sehingga akan memberikan gambaran bagi mekanisme penyelesaian yang terjadi. Selain itu untuk memperkuat argumentasi dalam rekomendasi proses penyelesaian lebih lanjut. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Konflik Hadirnya PTPN VII dan Hilangnya Hak Kelola Petani PTPN VII Cinta Manis berdiri berdasarkan SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 Tanggal 2 Februari 1981, tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumatera Selatan yang merupakan upaya pemerintah guna memenuhi Swasembada gula dalam negeri. Pada awalnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut mencapai 21.358 Ha. Penyediaan lahan pembangunan Perkebunan dan Pabrik Gula Cinta Manis 254 melalui SK Gubernur KDH tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981. Pemerintah dan perusahaan melakukan sosialisasi menjanjikan masyarakat akanmendapatkan ganti rugi, jaminan pekerjaan, fasilitas pendidikan, kesehatan. Tetapi kenyataannyapratek penyediaan lahan dilakukan melalui penggusuran secara paksa, peminggiran masyarakat, dan intimdasi oleh aparat keamanan, termasuk di wilayah Rengas dan Limbang Jaya. Tindakan tersebutmengakibatkan lahan pertanian masyarakat yang telah dikelola turun temurun beralih fungsi, menjadi bagian dari proyek perkebunan. Berdasarkan data pergerakan petani Rengas lahan masyarakat Rengas yang terkena dampak yaitu selus 2.535 Hektar, sedangkan yang diganti rugi 824 Hektar.Pengukuran kembali lahan dilakukan oleh masyarakat Desa Rengas berdasarkan pada peta desa dan berita acara ganti rugi oleh TIM 9 Pembebasan lahan, sedangkan untuk lahan di Desa Limbang Jaya seluas 641 Hektar lahan yang diambil alih oleh perusahaan. Struktur masyarakat pertanian, akhirnya bergeser sejak kehadirian perusahaan. Masyarakat beralih profesi menjadi buruh harian, merantau, dan harus meninggalkan desa untuk beberapa tahun lamanya mencari tempat menjadi buruh pertanian di daerah lain. Secara ekonomi adanya pergeseran sumber daya ekonomi tersebut secara alamiah berpengaruh pada kondisi sosiol ekonomi masyarakat. Perbedaan Landasan Klaim Logika hukum formal menjadi dasar klaim perusahaan terhadap lahan rakyat, misalkan lahan dilakukan ganti rugi dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, selain itu klaim lain yaitu lahan yang memiliki bukti tanam tumbuh sebagai salah satu bukti kepemilikan, sedangkan masyarakat memiliki klaim pengakuan lokal dalam memahami kepemilikan, luasan, batas dan hak kelola. Perbedaan kontruksi landasan klaim inilah yang menjadi pemicu kontestasi konflik lahan. Masyarakat desa Rengas dan Limbang Jaya serta masyarakat desa di Sumatera Selatan secara umum, diatur berdasarkan pemerintahan marga, dalam praktek pengaturan masyarakat berdasarkan Undang-Udang Simbur Cahaya. Penguasaan lahan batasan ladang dan mekanisme pengaturan pengelolaan lahan disebutkan secara jelas pada bab mengenai “Aturan Dusun dan Berladang”. Misalkan dalam pasal 27) Undang-undang Simbur Cahaya menyebutkan bahwa : “Jika orang yang berladang di marga asing hendaklah minta izin pada pasirahnya dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang 1 rupiah, dan itu uang pula pada orang banyak. Dan yang melanggar ini dapat kena denda 6 R “ Maling Utan”. dan pasal 28) “Jika orang yang numpang bertalang atau berkebun di tanah lain dusun atau marga hendak balik ke dusun sendiri, ia punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah”. Menurut Collins (2008), penguasaan lahan oleh masyarakat di Sumatera Selatan berdasarkan konsensus, satu komunitas dapat memberi hak kepada pendatang untuk mengelola tanah adat atau ulayat. Berbeda dari hak kepemilikan formal, hak pengelolaan oleh perorangan hanya berlangsung selama lahan itu ditanami. Jika lahan ditinggalkan atau tidak digarap lagi hak kepemilikan kembali kepada komunitas. Sejak berlakukanya hukum formal dalam pengakuan terhadap penguasaan lahan dan pengelolaa lahan, serta penghapusan pemerintahan marga. Dasar klaim yang selama ini hidup dan telah terinternalisasi dalam masyarakat menjadi lemah dihadapkan dengan pendekatan formal oleh negara dan perusahaan. Legitimasi perusahaan dengan hukum formal dalam konflik menjadi pemicu utama menjalar dan melembaganya konflik. INTENSITAS DAN DINAMIKA KONFLIK 255 Membaca Fase Konflik Masyarakata Desa Rengas Temuan penting dalam mapping konflik petani desa Rengas yaitu setting sosial politik telah memberikan kontribusi bagi hadirnya konflik sebagai respon alamiah dari setiap kebijakan yaang dianggap menegasikan rakyat. Secara historis konflik Rengas telah melalui dua fase prakondisi sosio politik yaitu pada masa sebelum reformasi (Orde Baru), dan pasca reformasi: Sebelum Reformasi (1981-1998) Kehadiran perusahaan perkebunan sejak tahun 1981, dengan praktek pembebasan lahan tidak transparan, tidak ada ruang dialogis menjadi akar historis lahirnya konflik yang masif dan berkelanjutan.Kondisi tersebut tergambar dalam tabel berikut: Tabel 1.Pemetaan Aktor dan Isu dalam Konflik Masyarakat Desa Rengas dan PT. PTPN VII Fase Sebelum Reformasi Fase Sebelum Reformasi Masyarakat Desa Rengas PT. PTPN VII (1981-1998) Isu dan Legitimasi Aktor Pendekatan Penyelesaian - Ganti rugi murah - Pembebasan lahan tidak transparan - Proses ganti rugi tanpa negosiasi - Penyerobotan lahan - Tindakan represif aparat - Sistem tenurial lokal/ kepemilikan adat - Kriyo (Kepala Desa) - Sebagian kepala keluarga - Sebagian tokoh masyarakat - Menolak ganti rugi - Melakukan protes dalam skala kecil - Litigasi (peradilan) - Tidak Tercapai - SK Mentan Nomor 076/Mentan/I/1981 tanggal 2 Februari 1981, tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumatera Selatan - SK Gubernur KDH tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 - Satgas dan Karyawan - Manajemen PT. PTPN VII (Humas) - Aparat kemananan (Tentara) - Pemerintah daerah (Tim 9) - Litigasi (peradilan) - Mediasi, melalui ganti rugi - Kerjasama dengan Pemerintah Daerah - Ganti Rugi Sebagian lahan masyarakat Sumber : Analisis Data Primer, Juni 2015 Fase sebelum reformasi (Orde Baru), ditandai dengan kuatnya dominasi negara terhadap rakyat, sehingga tidak ada ruang bagi kehidupan yang demokratis. Penindasan dan peminggiran rakyat demi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tontonan dan direspon melalui perlawanan tanpa kekerasan dari rakyat. Setting sosial politik merupakan prakondisi lahirnya konflik yang terjadi antara masyarakat Rengas dengan perusahaan dan negara pada waktu itu. Selain prakondisi sosial politik Orba yang membingkai konflik, isu dan kondisi riil yang mendasari konflik yaitu pertama; praktek pembebasan lahan yang tidak transparan, 256 kedua; ganti rugi lahan dengan harga yang sangat murah, ketiga; proses ganti rugi tanpa negosiasi, keempat; tindakan refresif aparat keamanan saat melakukan pembebasan lahan. Dasar legitimasi yang mendasari klaim masyarakat terhadap kepemilikan lahan yaitu sistem tenurial lokalatau hukum adat, sedangkan PTPN VII dengan dasar klaim legal yaitu 1) SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 tanggal 2 Februari 1981, tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumatera Selatan. 2) SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981, tentang penyediaan lahan. Aktor yang terlibat dalam kontestasi konflik yaitu pertama pihak masyarakat Rengas yaitu Kriyo/Kepala Desa. Pada fase ini masih sedikit masyarakat yang terlibat dan ambil bagian dalam penolakan terhadap kehadiran perusahaan. Strategi perlawanan diawal masuknya perusahaan dilakukan oleh aktor-aktor Rengas yaitu menolak ganti rugi, melakukan protes dalam skala kecil dalam lingkup ikatan kekeluargaan. Dari pihak perusahaan aktor yang terlibat dalam konflik yaitu dari Manajemen Perusahaan (Humas), Satgas dan Karyawan, aktor aparat keamanan (Tentara), Pemerintah Daerah (Tim 9). Untuk memuluskan rencana dan operasional perusahaan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan yaitu dengan strategi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, mediasi, ganti rugi dan jalur litigasi (peradilan). Tahun 1996 akhir fase pertama masyarakat mengalihkan strategi perlawanan dengan jalur litigasi (peradilan). Upaya litigasi ditempuh oleh kelompok masyarakat Desa Rengas yang merasa belum pernah menerima ganti rugi dari lahan mereka yang digusur oleh perusahaan. Upaya litigasi dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh kuasa hukum, Syahziar Syaarani, S.H., dan gugatan dimenangkan oleh masyarakat Desa Rengas hingga sampai ke Mahkamah Agung (MA RI). Keputusan Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa lahan yang belum dibebaskan adalah milik warga masyarakat Desa Rengas, tetapi sejak ditetapkan keputusan tersebut tidak dilakukan eksekusi oleh pengadilan, hingga berakhirnya fase konflik di era Orde Baru. Kendala lain menggunakan jalur litigasi yaitu tidak semua masyarakat mampu membayar kuasa hukum, sehingga tidak semua lahan masyarakat yang memiliki surat tersebut dimenangkan oleh pengadilan, padahal menurut Misbah, berdasarkan pendapat kuasa hukum pada waktu kasus yang sama, sehingga kemenangan salah satu tuntutan dianggap kemenangan semua masyarakat. Pasca Reformasi (1998-Sekarang) Memasuki era reformasi, di mana kebebasan mulai diadikan ukuran dalam pengembilan kebijakan, terutama dalam pelibatan partisipasi masyarakat, telahmemberikan pengaruh penggunaan strategi dan trik lebih variatif dalam konstelasi konflik yang terjadi antara masyarakat Rengas dan perusahaan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Tabel 2. Pemetaan Aktor dan Isu dalam Konflik Masyarakat Rengas dan PT. PTPN VIIFase Reformasi Fase Reformasi Masyarakat Rengas PTPN VII (1998-Sekarang) Isu dan Legitimasi - Penyerobotan Lahan - Tindakan refresif aparat (Meninggalnya Kryo) - Kemenangan Gugatan di MA - SK Mentan No. 076/Mentan/I/1981 tanggal 2 Februari 1981, tentang izin prinsip pendirian perkebunan tebu dan pabrik di Sumatera Selatan 257 Aktor Pendekatan Penyelesaian - Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - WALHI Sum-Sel (Pihak ketiga) - LBH Palembang (Pihak ketiga) - SPI (Pihak Ketiga) - Perjuangan kolektif - Aksi massa, protes - Konfrontasi - Mediasi - Reklaiming - SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan No. 379/I/1981 tanggal 16 November 1981 - Satgas dan Karyawan - Manajemen PT. PTPN VII (Humas) - Litigasi - Mediasi - Menarik diri Sumber: Analisis Data Primer, Juni 2015 Isu pada fase reformasi merupakan lanjutan dari fase sebelumnya. Kemenangan di MA RI menjadi alas legitimasi formal dari masyarakat, setelah sebelumnya difase pertama hanya mengandalkan klaim melalui sistem tenurial lokal, sedangkan dasar klaim dan ligitimasi perusahaan masih sama yaitu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Selatan, serta dokumen ganti rugi. Memasuki fase reformasi aktor masyarakat yang terlibat perlawanan terhadap perusahaan kian meningkat, aktor tersebut misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan didukung oleh hampir semua lapisan masyarakat. Meningkatnya jumlah aktor dan massa yang terlibat dalam konflik tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial politik yang mulai terbuka. Konfrontasi mulai diperankan dalam panggung perseteruan antara masyarakat dengan perusahaan. Mengimbangi semakin massif gerakan masyarakat, perusahaan tetap dengan pendekatan hukum formal dan memperkuat dukungan ekonomi politik terhadap stakeholder untuk terlibat dalam konstelasi konflik yaitu aparat keamanan dalam hal ini aparat kepolisian. Fase ini melahirkan banyak pendekatan yang dilakukan oleh kedua belahpihak, dan peran pemerintah mulai hadir dalam ruang-ruang dialogis mencari jalan solusi yang tak pernah tercapai. Aktor lokal telah membawa konflik ke ruang eskalasi yang memucak menjadi konflik kekerasan. Mobilisasi massa secara besar-besaran dan tindakan menguasai lahan menjadi strategi penting dalam konflik bagi masyarakat. Tindakan tersebut dibalas dengan tindakan pencegahan oleh perusahaan didukung oleh satgas dan aparat keamanan, tetapi akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap konflik yang tak kunjung usai sehingga situasi konflik mengarah pada tindak kekerasan dilakukan oleh kedua bela pihak. Tahun 2009 puncak dari konflik yang meletus menjadi kekerasan terbuka antara masyarakat, perusahaan dan aparat keamanan. Menurut Abdul Kholek (2011), tercatat 12 korban penembakan masyarakat Desa Rengas saat terjadi konflik kekerasan di lahan yang disengketakan. Kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Brimobda Sumatera Selatan dengan melakukan pengamanan asset perusahaan merupakan tindakan kekerasan dan dianggap sebagai puncak krisis dari konflik. Pasca konflik kekerasan muncul dukungan dari unsur masyarakat sipil, memberikan kekuatan baru dan semakin sistematisnya gerakan yang dibangun oleh 258 masyarakat Desa Rengas. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan dan Serikat Petani Indonesia Sumatera Selatan adalah institusi yangberperan cukup penting dalam upaya strategi konfrontasi melalui aksi massa sistematis, dan melakukan desakan kepada pengambil kebijakan. Institusi lain adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang lebih menekankan pada asfek pelanggaran HAM atas penembakan warga Desa Rengas. Tahun 2010 masyarakat yang didukung oleh unsur masyarakat sipil melakukan reklaiming lahan yang disengketakan seluas 1.529 Ha. Reklaiming yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan akhir dikarenakan proses penyelesiaan melalui mediasi dan dialog tidak menghasilkan kesepakatan yang diinginkan. Landasan klaim reklaiming yaitu kemenangan di MA, sistem tenurial lokal, hasil pengukuran kembali oleh masyarakat secara partisipatif, dan didapatkan informasi mengenai perusahaan tidak memiliki HGU dilahan yang disengketakan. Hingga kini masyarakat telah mengelola lahan tersebut, dan membagikan kepada seluruh warga Rengas yang ikut melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Konflik Masyarakat Desa Limbang Jaya, sebagai Eskalasi Pemicu utama konflik Limbang Jaya dan PTPN VII Cinta Manis, yaitu kemenangan masyarakat Rengas dalam menguasai kembali lahan yang dikelola oleh perusahaan, melalui upaya reklaiming. Kasus Limbang Jaya tidak ditemukan catatan sejarah perlawanan masyarakat dalam menentang hadirnya perusahaan.Awal terseretnya masyarakat Limbang Jaya dalam konstelasi konflik dengan perusahaan yaitu saat bergabungnya beberapa aktor kedalam organisasi “Gerakan Petani Penesak Bersatu” (GPPB), sejak tahun 2011. Berdirinya GPPB sebagai pelembagaan gerakan perlawanan masyarakat terhadap PTPN VII Cinta Manis. Gerakan ini terinspirasi dari kemenangan masyarakat Rengas dalam merebut kembali lahan yang dikelola oleh perusahaan sejak tahun 1981, melalui aksi reklaiming. GPPB mencakup wilayah 7 (tujuh) kecamatan dan 22 Desa dengan jumlah anggota lebih kurang 6.611 KK. Luas lahan yang dituntut oleh GPPB yaitu 21.000 hektar, lahan tersebut tesebar di 7 (tujuh) kecamatan, termasuk didalamnya wilayah Desa Limbang Jaya dengan luas 641 Hektar. Tuntutan GPPB yaitu mendesak pengembalian lahan yang dikelola oleh perusahaan dengan dasar argumentasi sebagai berikut pertama; proses ganti rugi yang masih bermasalah; kedua; keberadaan perusahan merubah struktur masyarakat dari petani produktif menjadi buruh tani; ketiga; minimnya penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal; keempat; tindakan represif aparat keamanan; kelima; minimnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Berbagai strategi dilakukan oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Gerakan yang dibangun dengan cakupan yang relatif luas mengakibatkan rentang kendali kurang maksimal. Pengalaman perlawanan petani Rengas serta strategi yang diterapkan mangadopsi pola-pola yang hampir sama. Isu pembebasan lahan dan ganti rugi lahan dimunculkan kembali untuk membangkitkan semangat aktor dalam memobilisasi massa di masing-masing desa untuk masuk kedalam ruang konfliktual. Intensitas konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Limbang Jaya dan PTPN VII Cinta Manis, semakin meningkat saat pola konfrontasi mulai menjadi strategi utama yang dimainkan oleh aktor terlibat konflik.Banyak aktor yang dikriminalisasikan dalam konflik tersebut, kondisi ini telah menarik aparat keamanan kedalam kontestasi konflik. Pola ini hampir sama dengan kasus Desa Rengas dan konflik pertanahanlain yang terjadi di Indonesia. Puncaknya yaitu ketiga ratusan aparat kepolisian besenjata lengkap masuk ke Desa Limbang Jaya, untuk menangkap salah satu aktor penggerak, pendekatan represif telah 259 menyulut kemarahan masyarakat sehingga terjadinya bentrok hingga beberapa masyarakat terkena tembak, dan satu warga Angga (12) Tahun meninggal dunia terkena peluru tajam oleh Brimob di Desa Limbang Jaya pada tanggal 27 Juli 2012. Aksi massa, kriminalisasi, tindakan represif dan jatuhnya korban menjadi tontonan wajib setiap kontestasi konflik pertanahan. Dalam persfektif perusahaan pengerahan aparat keamanan untuk pengawalan asset dan mendorong konflik keranah litigasi, merupakan trik untuk membentengi mereka agar tidak terlibat langsung kedalam konflik terbuka, shock therapy bagi masyarakat bahwa perlawanan tersebut sebagai bentuk penentangan terhadap negara. Disisi lain aktor gerakan masyarakat memanfaatkan kekerasan untuk menaikkan isu dan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik. Tetapi dalam kasus Limbang Jaya, kekerasan dan kriminalisasi ternyata berimbas pada menurunnya semangat dan totalitas keterlibatan masyarakat, serta banyak aktor-aktor kunci yang menarik diri dari kontestasi konflik, sehingga pola konflik Rengas yang berujung dengan reklaiming tidak mampu direalisasikan oleh masyarakat Limbang Jaya maupun GPPB. Kondisi ini mengalihkan kembali konflik keranah laten, dan menjadi bara dalam sekam yang bisa menjalar dan meletus kembali dalam konflik yang lebih besar dan sistemik. Upaya Penyelesaian Konflik Jalur Advokasi NGO (Non Goverment Organization) Konflik di Desa Rengas mulai didampingi secara intensif oleh NGO pasca penembakan 12 petani di lahan yang disengketakan tahun 2009, sedangkan konflik di Limbang Jaya dua tahun kemudian setelah terhimpun dalam GPPB tahun 2011. Advokasi Rengas oleh WALHI Sumatera Selatan, SPI, dan LBH Palembang, sedangkan di Desa Limbang Jaya melalui organisasi lokal yaitu Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB). Penyelesaian konflik baik Rengas maupun Limbang Jaya melalui jalur advokasi NGO, menitikberatkan pada strategi bertindak secara terorganisir, sistematis, propaganda, lobby, aksi massa, konfrontasi, dan mediasi (Kholek, 2011). Pola-pola tersebut diterapkan dengan metode yang sama dalam kedua kasus konflik tersebut, meskipun dalam rentang waktu yang berbeda. Tabel 3. Penyelesaian Konflik Jalur Advokasi Kasus Desa Rengas dan Limbang Jaya Jalur Advokasi No Subjek Konflik Aksi Massa Konfrontasi Lobbi Mediasi 1 Petani Rengas + + - - 2 Limbang Jaya + + - - Sumbe : Analisis Peneliti, 2015 Tabeltersebut memberikan gambaran mengenai jalur advokasi NGO bersama masyarakat sebagai subjek konflik. Baik kasus Desa Rengas maupun Desa Limbang Jaya semua terlibat dalam upaya penyelesaian melalui lobby, mediasi, aksi massa, dan konfrotasi. Kedua konflik tersebut lebih dominan menitikberatkan pada pendekatan jalur aksi massa, dan kofrontasi atau perlawanan langsung. 260 Aksi massa dan konfrontasi bukan sebagai langkah akhir dalam penyelesiaan konflik tetapi sebagai upaya awal untuk mendesak pihak yang berwenang. Misalkan dalam kasus Rengas pasca penembakan warga yang menduduki lahan, tercatat beberapa kali upaya untuk mendesak pemerintah dalam penanganan konflik lahan. Isu yang didorong dalam berbagai aksi massa yaitu agar pengambil kebijakan segera mengambil tindakan penyelesaian terhadap konflik yang telah berlarut-larut tersebut. Keterlibatan masyarakat Desa Rengas dan Desa Limbang Jaya dalam aksi massa di level lokal, maupun nasional sebagai wujud perjuangan masyarakat untuk mendapatkan jalan penyelesiaan koflik. Jika dianalisis aksi massa sebagai langkah awal mendorong penyelesiaan konflik, sepertinya capaian dari strategi tersebut masih minim dalam mendorong penyelesaian konflik, karena dalam setiap aksi massa dari level lokal sampai nasional respon pemangku kepentingan tetap sama yaitu tidak memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik, dan terkesan mengambil jarak terhadap konflik, serta saling lempar tanggung jawab. Kasus yang menimpa petani Desa Rengas yang melakukan aksi reklaiming sebagai wujud nyata dari upaya konfrontasi, setelah jalur aksi massa mendesak dan mendorong pemangku kepentingan untuk hadir dalam ruang penyelesaian dianggap gagal. Upaya reklaiming sebagai jalur penyelesaian jangka pendek yang dianggap paling rasional oleh masyarakat, untuk memastikan lahan yang disengekatan dapat dikelola oleh masyarakat. Meskipun reklaiming tidak bisa dianggap sebagai penyelesiaan sengketa, tetapi dalam persfektif masyarakat jalan ini sebagai bentuk riil perlawanan sesungguhnya, terhadap perusahaan dan negara yang tidak hadir dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah.Tetapi untuk kasus Limbang Jaya, upaya reklaiming tidak memberikan hasil, dikarenakan tidak adanya basis historis dari perlawanan masyarakat, sehingga upaya konfrontatif tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Jalur Mediasi Pemangku Kepentingan Upaya advokasi dilakukan oleh masyarakat sipil, telah memberikan efek positif dengan adanya tindak lanjut oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, DPRD/RI, BPN, Kementerian BUMN, Kepolisian. Tetapi mediasi sebagai jalan normatif yang ditempuh oleh pemangku kepentingan dalam meminimalisir dampak negatif dari konflik yang terjadi. Sehingga mediasi belum merujuk pada penyelesaian yang komprehensif, dan berkelanjutan. Mediasi yang dipraktekkan hanya sebatas peredam sementara dari pertikaian kedua bela pihak yang berkonflik. Kasus Desa Rengas maupun Limbang Jaya tercatat beberapa kali jalur mediasi dilakukan, dalam upaya mencari jalan penyelesaian yang diterima oleh kedua bela pihak.Tuntutan masing-masing pihak dalam praktek mediasi, memang tidak ditemukan titik kesepakatan. Poin yang ditawarkan masyarakat dianggap tidak logis, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah, dan dianggap akan memicu pelanggaran hukum menurut persfektif aparat penegak hukum. Pada sisi lain, perwakilan masyarakat beranggapan bahwa tawaran tersebut sebagai akar dari penyelesaian konflik yang berlarutlarut. Dilevel kebijakan pemerintah, dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 896/KPTS/I/2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan Antara Petani/Warga Sekitar Perkebunan Cinta Manis Dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir. Tim terpadu menggunakanmetode verifikasi yaitu komparasi data warga yang mengklaim lahan dengan data ganti rugi dari PTPN VII Cinta Manis berdasarkan bukti legal. Tim terpadu kinerja tidak efektif kerena perspektif penyelesaian konflik lahan hanya pada dokumen ganti rugi, bukti kepemilikan lahan secara formal, tanpa melibatkan 261 catatan-catatan historis mengenai peristiwa pembebasan lahan, serta pengakuan terhadap hukum adat mengenai kepemilikan lahan masyarakat yang telah tumbuh secara turun temurun. Fakta tersebut sebagai salah satu kelemahan dalam penyelesaian konflik yang dimediasi oleh pemerintah, sehingga win-win solution tidak pernah terwujud dalam ruang mediasi. Baik kasus petani Desa Rengas maupun masyarakat Desa Limbang Jaya, meskipun adanya tim terpadu penyelesaian konflik lahan yang dibentuk oleh pemernitah, tetapi belum mampu memberikan penyelesaian yang berkelanjutan,karena ruang penyelesaian yang ditempuh tidak menyentuh kepada substansi permasalahan, sehingga konflik hanya diredam sementara, dan kemungkinan besar pegulangan konflik menjadi kekerasan sangat terbuka dikemudian hari. 5. KESIMPULAN Temuan dalam penelitian yaitu, pertama;Akar persoalan utama lahan kelola masyarakat yang telah digarap turun-temurun, masuk areal penyedian lahan oleh pemerintah daerah pada waktu itu, sehingga tertutupnya akses kelola masyarakat terhadap lahan. kedua; dinamika konflik masyarakat Rengas dengan PTPN VII Cinta Manis, mengalami pasang surut tercatat konflik telah memasuki dua fase yaitu saat Orde Baru dan Pasca Reformasi.ketiga; Konflik di Desa Limbang Jaya, sebagai eskalasi konflik Rengas yang dianggap sebagai kemenangan petani dalam upaya mengambil alih lahan dengan melakukan reklaiming.keempat;Pasca reformasi eskalasi konflik kian meningkat dan berubah menjadi kekerasan yang sitemik, serta meluasnya keterlibatan aktor dalam arena konflik. kelima;Proses penyelesaian yang dilakukan baik melalui jalur advokasi NGO maupun jalur mediasi oleh pemerintah tidak memberikan ruang penyelesaian yang mengakomodir kepentingan kedua bela pihak yang berkonflik secara seimbang. keenam;Kelemahan penyelesaian yang sudah dilakukan yaitu, belum dipraktekkan pola mediasi secara substantif dalam penyelesaian. Serta tidak hadirya pemangku kepentingan dalam ruang penyelesaian.Masih minimnya komitmen pengambil kebijakan dalam penyelesaian konflik.ketujuh;Selain itu kelemahan dalam aspek pendekatan penyelesaian konflik, pengambil kebijakan terkesan prosedural, melalui hukum formal, sehingga hasilnya tidak mengakomodir kepentingan masyarakat, yang selalu tersubordinat dari proses tersebut. 6. DAFTAR PUSTAKA Alfitri, dkk. 2013. Model Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai kearifan Lokal “Tepung Tawar” pada Komunitas Talang Sejemput Lahat Sumatera Selatan. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Alfitri dan Abdul Kholek. 2013. Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu). Prociding Konferensi Nasional Sosiologi I, Palembang: APSSI-Magister Sosiologi Unsri. Cain, Allan. 2010. Research and practice as advocacy tools to influence Angola’s land policies. Jurnal Internasional Environment and Urbanization, October 2010; vol.22, 2: pp.505522.http://online.sagepub.com.www.ezplib.ukm.my/search/results. Collins, Elizabeth Fuller. 2008. Indonesia Dikhianati. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Coombes, Brad et all. 2012. Indigenous geographies I : mare resource conflicts? The complexities in Indigenous land and environmental claims. Jurnal Internasional Progress in Human Geography, December 2012; vol. 36, 6: pp. 810-821., first 262 published on December 13, 2011http://online.sagepub.com.www.ezplib.ukm.my/search/results. Edward, Allan Barsky. 2000. Conflict Resolution for the Helping Professions. Canada: Brooks/Cole Thomson Learning. Galang, Asmara, dkk. 2010. Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai – Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/297. Diakses Senin, 30 Mei 2012. Glover, Troy d. Et all. 2008. Social Ethics of Landscape Change : Toward CommunityBased Land-Use Planning. Jurnal Internasional Qualitative inquiry, April 2008; vol. 14, 3: pp. 384401.http:/online.sagepub.com.www.ezplib.ukm.my/search/results. Kholek, Abdul. 2011. Strategi Advokasi NGO dalam Konflik Pertanahan. Studi Tentang Strategi Advokasi Walhi Sumatera Selatan dan LBH Palembang dalam Konflik Pertanahan Petani Rengas versus PTPN VII Cinta Manis.Tesis. Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Kim, Annette M. 2011. Talking Back: The role of Narrative in Vietnam’s Recent Land Compensation Changes. Jurnal Internasional Urban Studies, Februari vol 48, 3: pp. 493-508. http:/online.sagepub.com.www.ezplib.ukm.my/search/results. Pratap, Dinesh. 2010. Community Participation and Forest Policies in India: An Overview. Jurnal Internasional Social Change, September 2010; Vol. 40, 3: pp. 235256.http:/online.sagepub.com.www.ezplib.ukm.my/search?fulltext=resolution+co nflict+model+land+and+forest&x=26&y=16&src=hw&andorexactfulltext=and& submit=yes. Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu – Isu Konflik Kontemporer. Jakarta : Kencana Media Group. Arsip Data Konflik Pertanahan yang Didampingi Walhi Sum-Sel Tahun 2007-2010”, Sumber Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel, 2009. Arsip Data Konflik Pertanahan yang Didampingi Walhi Sum-Sel Tahun 2010-2011”, Sumber Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel, 2012. Arsip Data Konflik Pertanahan yang Didampingi Walhi Sum-Sel Tahun 2010-2014”, Sumber Dokumen Advokasi Walhi Sum-Sel. Koran Sumatera Ekspres. 12 April 2012. Pertemuan KOMNAS HAM dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. 263 REFORMA AGRARIA BIDANG KEHUTANAN: SEBUAH TINJAUAN POLITIK SIMBOLIK Ferdinal Asmin Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), email: [email protected] Abstrak Reforma agraria bidang kehutanan merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan konflik-konflik kehutanan. Akan tetapi, kebijakan kehutanan nasional dan daerah belum mampu memberikan dukungan yang efektif bagi keberhasilan reforma agraria. Tulisan ini menjelaskan fakta-fakta reforma agraria bidang kehutanan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyukseskannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan mengelaborasi konsep politik simbolik melalui kajian peraturan dan dokumen-dokumen terkait. Pembahasan dilakukan pada tingkat makro (nasional) dan tingkat mikro (daerah) dengan mengambil contoh implementasi skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di Sumatera Barat. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kemajuan reforma agraria bidang kehutanan melalui program dan kegiatan perhutanan sosial (social forestry) secara nasional masih belum maksimal, meskipun pada tingkat daerah, gencarnya gerakan PHBM di Sumatera Barat dapat menjadi salah satu preseden baik bagi keberhasilan reforma agraria bidang kehutanan di daerah. Namun secara keseluruhan, perhutanan sosial masih dianggap sebagai simbol klaim keberpihakan pada masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Rekomendasi dari tulisan ini adalah mendorong perubahan konsep perhutanan sosial menjadi prioritas utama kebijakan kehutanan dan mendorong rimbawan birokrat menjadi wirausahawan sosial. Kata Kunci: Kehutanan Sosial, Reforma Agraria, Wirausahawan Sosial Abstract Land reform of forestry sector is one of the important ways to resolve the forestry conflicts. However, the national and local forestry policies have not been able to support effectively and successfully land reform. This article explained the facts of the land reform in forestry sector and provided recommendations to make a successfully land reform. The method is case study by elaborating a concept of symbolic politics through regulations and related documents review. The discussion was focused on national and local level by taking case aboutthe implementation of community based forest management (CBFM) in West Sumatra. The result revealed that the progress of land reform through social forestry program at national level was not satisfied, even though at local level, the increasing of CBFM movement in West Sumatra can be one of good precedents for successfully land reform of forestry sector. But overall, social forestry may be still considered as a symbol of alignments to local and indigenous communities. The recommendations from this article are encouraging the change of social forestry concept into the main priority of forestry policies and encouraging a forester into a social entrepreneur. Keywords: Land Reform, Social Entrepreneur, Social Forestry 264 1. PENDAHULUAN Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merekam 1,772 kasus konflik agraria sejak tahun 2004 sampai 2015 yang mencakup luasan sekitar 7 juta ha (KPA 2016). Konflik agraria yang terjadi menyangkut banyak sektor pembangunan, termasuk kehutanan. Konflik sumber daya hutan antara pemerintah dan masyarakat lokal (terutama petani) sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagaimana diuraikan oleh Simon (2006), konflik berawal dari eksploitasi kayu jati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pengembangan perkebunan (cultuurstelsel) secara besar-besaran sehingga ekosistem hutan jati di Pulau Jawa mengalami kerusakan. Pada tahun 1849, Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun hutan tanaman jati. Untuk mendukung pembangunan hutan tanaman jati tersebut, Pemerintah Hindia Belanda membuat undang-undang tentang agraria pada tahun 1870 dan undang-undang tentang kehutanan tahun 1927 (Bos-ordonantie) yang mengikis hak ulayat masyarakat Jawa pada saat itu. Kepentingan masyarakat diakomodir dengan mengembangkan sistem taungya dan/atau tumpangsari dalam pembangunan hutan tanaman jati. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, Pemerintah Hindia Belanda mampu membuat kesepakatan dengan tokoh masyarakat adat untuk menentukan batas-batas hutan yang seringkali disebut dengan hutan register. Konflik berlanjut pada era orde lama, era orde baru, dan era reformasi sebagaimana dijelaskan oleh Barber (1998) dan Simon (2006). Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan semakin banyak kendala sebagaimana yang terjadi di Pulau Jawa (Maryudi dan Krott 2012). Sedangkan di luar Pulau Jawa, konflik sumber daya hutan disebabkan oleh klaim ulayat terhadap kawasan hutan negara dan ketidakadilan pemerintah dalam pemberian hak kelola sumber daya hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pihak korporasi seperti yang diuraikan oleh Suharjito (2013). Isu degradasi hutan dan deforestasi juga mendorong kompleksitas konflik kehutanan di Indonesia. Hutan primer semakin berkurang dari sekitar 162 juta ha pada tahun 1950 (FWI 2011) menjadi sekitar 46 juta hektarpada tahun 2014 (KemenLHK 2015).Pembahasan konflik kehutanan kemudian dikaitkan dengan problematika degradasi hutan dan deforestasi. Penanganan konflik kehutanan dilakukan dengan mengembangkan berbagai program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Perum Perhutani yang menguasai kawasan hutan negara di Pulau Jawa melaksanakan program Prosperity Approach pada tahun 1974, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982, Perhutanan Sosial (PS) pada tahun 1985, dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 (Simon 2006). Di luar Pulau Jawa, programprogram sosial kehutanan baru muncul pada awal tahun 1990-an dengan program Bina Desa Hutan atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1991-2003, Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 1995, Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi sejak tahun 2004, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak tahun 2008 (Sardjono 2013). HKm, HTR, dan HD merupakan programprogram soft agrarian reformyang sedang berjalan saat ini (Daryanto 2014) dan kemudian dikenal sebagai perhutanan sosial atau juga selalu diidentikkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Selain dari itu, pemerintah juga mengakomodir implementasi hutan adat sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012. 265 Realisasi perizinanHKm, HTR, dan HD ternyata masih sangat rendah dibandingkan dengan perizinan terhadap korporasi dalam bentuk pemanfaatan hutan alam (IUPHHKHA) dan hutan tanaman (IUPHHK-HTI). Meskipun hampir 2 juta ha kawasan hutan telah ditetapkan sebagai areal kerja HTR, HKm, dan HD, perizinan yang didapatkan masyarakat lokal baru mencapai sekitar 374,000 ha(KemenLHK 2015). Jumlah luasan izin tersebut masih sangat jauh berbeda dengan jumlah luasan izin bagi korporasi yang mencapai sekitar 31 juta hektar. Fenomena ini menarik untuk dikaji dengan pertanyaan kenapa realisasi program perhutanan sosial tersebut berjalan sangat lambat. Hambatan birokrasi pemerintah pusat dan daerah sering diklaim sebagai kendala utama. Akan tetapi, agresivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pembelajaran penting karena capaian target perhutanan sosial sekitar 11% dari 374.000 ha izin yang sudah dikeluarkan di seluruh Indonesia. Sumatera Barat kemudian dikenal sebagai provinsi percontohan perhutanan sosial di Indonesia. Pertanyaannya selanjutnya adalah politik apa yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana sebenarnya politik agraria bidang kehutanan pada tingkat nasional berkaitan dengan program perhutanan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan reforma agraria bidang kehutanan di Indonesia secara umum dan di Sumatera Barat secara khusus dengan menggunakan pendekatan politik simbolik. Perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan reforma agraria bidang kehutanan telah menjadi simbol politik agraria yang dijalankan birokrasi kehutanan mulai dari tingkat nasional sampai daerah. Fakta-fakta tentang perhutanan sosial dapat memberikan gambaran keberhasilan reforma agraria bidang kehutanan. Oleh karena itu, konsep politik simbolik yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai aksiaksi simbolik perhutanan sosial yang dijalankan birokrat menurut kepentingannya dan yang merepresentasikan manipulasi keberpihakan untuk tujuan tertentu. 2. TINJAUAN PUSTAKA Persoalan-persoalan lahan atau tanah untuk pertanian seringkali menjadi fokus utama reforma agraria di Indonesia, walaupun sebenarnya reforma agraria dimaksudkan untuk hal yang lebih luas dari hal tersebut. Reforma agraria seharusnya lebih dilihat sebagai upaya perubahan atau perombakan sosial yang dibangkitkan dari kesadaran penuh untuk mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat (Soetarto dan Hermansah 2007). Dalam konteks pembangunan kehutanan, reforma agraria diharapkan menjamin tata kelola kehutanan yang lebih baik dan adil dengan penataan distribusi penguasaan lahan hutan negara kepada masyarakat lokal (Suharjito 2013). Penguasaan atas lahan tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan semata, namun juga harus mencakup kepastian hak-hak yang ada di dalam penguasaannya (land tenure security) dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi tersebut, program HTR, HKm dan HD sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan reforma agraria bidang kehutanan yang memperluas akses sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi bagi rimbawan birokrat, program HTR, HKm, dan HD lebih dikenal sebagai bagian dari program perhutanan sosial, termasuk hutan adat yang kemudian dikategorikan sebagai hutan hak. Istilah perhutanan sosial sering digunakan sebagai terjemahan dari social forestry. Pada banyak literatur di Indonesia, istilah ini juga ditulis dengan kehutanan sosial seperti yang digunakan Simon (2006). Kehutanan sosial merupakan suatu strategi perencanaan dan implementasi yang mendorong pelibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan untuk memperbaiki kondisi sumber-sumber mata pencaharian masyarakat (Wiersum 266 2004). Beberapa literatur juga mengidentikkannya dengan hutan masyarakat (community forest).Dalam perspektif yang lebih luas, istilah perhutanan sosial, kehutanan sosial, dan hutan masyarakat sering diklasifikasikan sebagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management).Molnar et al. (2011) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) adalah pengelolaan hutan dan kebun wanatani oleh masyarakat atau pemilik lahan skala kecil, termasuk juga pengelolaan hutan negara yang sebagian besar diklaim sebagai hak dan milik adat menurut hukum dan praktek lokal. PHBM merupakan sebuah paradigma kuat yang berkembang dari kegagalan tata kelola hutan negara untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dan distribusi akses dan manfaat secara merata (Guiang et al. 2001).Molnar et al. (2011) kemudian menyebut ada hubungan langsung antara reforma tenurial dan perkembangan PHBM. Pendapat tersebut sebelumnya juga telah ditegaskan oleh Bernstein et al. (2010) bahwa reforma tenurial dan pelibatan masyarakat dalam tata kelola dan pengelolaan hutan dimaksudkan untuk meningkatkan akses rumah tangga petani dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya hutan. Berdasarkan hal tersebut, istilah perhutanan sosial yang dalam 10 tahun terakhir gencar diperkenalkan oleh pemerintah dapat dinilai sebagai respon terhadap desakan reforma agraria bidang kehutanan. Realisasi kebijakan reforma agraria bidang kehutanan selalu dipertanyakan karena tidak ada kebijakan yang konkrit. Dalam situasi demikian, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ternyata mampu mengelola situasi untuk meyakinkan publik bahwa perubahan sedang dilakukan. Peluncuran skema HTR, HKm, dan HD memberikan kesan bahwa perubahan telah dan akan dilakukan. Skema ini kemudian menjadi simbol bagi harapan perubahan yang diinginkan publik. Simbol dapat berupa istilah-istilah atau isyarat-isyarat yang membangkitkan keyakinan dan potensi sebuah situasi (Edelman 1971; Edelman 2001). Sebagai bagian dari proses politik, penggunaan simbol adalah sesuatu hal yang mungkin terlihat berhasil, namun kebijakan yang dibuat selanjutnya juga dapat menjadi kurang mendukung (Edelman 1977). Gugatan hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap definisi hutan adat dapat juga disebabkan oleh ketidakjelasan implementasi HTR, HKm, dan HD yang secara simbolik dinilai berbeda dengan hutan adat. Setiap kebijakan yang dilahirkan pada umumnya memiliki simbol (Newig 2007) dan kegagalan proses deliberasi dapat menyebabkanpenggunaan simbol menjadi semakin nyata (Niemeyer 2004). Kajian politik simbolik berguna untuk mendorong perbaikan proses-proses deliberasi agar reforma agraria bidang kehutanan dapat mencapai keberhasilan. Kajian ini bukan hanya dipakai untuk mengkritisi sebuah retorika kebijakan, tetapi seharusnya digunakan untuk menjelaskan kesenjangan antara kodifikasi dan implementasi (Matten 2003). Akan tetapi, politik simbolik cenderung dimaknai sebagai sebuah kritik terhadap kebijakan yang kurang memadai dan ditujukan untuk menyalahkan pengambil kebijakan (Blühdorn 2007).Dalam kajian ilmu lingkungan, politik simbolik merupakan aksi-aksi yang menggantikan opsi-opsi terbaik dan deliberasi strategi melalui fragmentasi kepentingan masyarakat, kesan-kesan sistem politik, menghindari konsekuensi yang tidak mengenakkan, dan mementingkan elit (Blühdorn 2007). Oleh karena itu, terkait dengan reforma agraria bidang kehutanan, kajian politik simbolik didefinisikan sebagai aksi-aksi simbolik perhutanan sosial yang dijalankan birokrat menurut kepentingannya dan yang merepresentasikan manipulasi keberpihakan untuk tujuan tertentu. 3. METODE PENELITIAN 267 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi secara sistematis terhadap suatu kasus yang memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana sesuatu terjadi (Berg 2001). Kasus dalam hal ini adalah hal-hal yang terikat pada sistem, waktu, tempat, atau ruang serta satu atau lebih program, kejadian, individu, atau aktivitas yang akan dipelajari (Suharjito 2014). Dalam penelitian ini, fokus kasus yang dipelajari adalah terkait dengan program-program perhutanan sosial skala nasional dan daerah yang diklaim sebagai salah satu bentuk kebijakan reforma agraria bidang kehutanan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan kajian dokumen. Observasi dilakukan pada berbagai kesempatan pertemuan dan diskusi publik terkait dengan perhutanan sosial di Sumatera Barat, sedangkan kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan perhutanan sosial, seperti publikasi ilmiah, dokumen laporan pemerintah, dan peraturan-peraturan terkait. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang merupakan salah satu alat penelitian kualitatif yang biasa digunakan untuk menentukan keberadaan dan makna dari konsep, istilah, dan kata-kata (Stan 2010). 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1.1. Klaim Perhutanan Sosial sebagai Simbol Keberpihakan Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta pada tahun 1978 yang bertema Forest for People menjadi momen penting meluasnya pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. PHBM berawal dari fokus untuk menangani permasalahan degradasi hutan dan deforestasi (Poffenberger 2006; Sam 2011; Teitelbaum 2014), yang selanjutnya PHBM juga menjadi bentuk perluasan akses masyarakat terhadap hutan dalam menangani isu-isu pembangunan (Charnley dan Poe 2007). Konsep-konsep PHBM berkembang pada tahun 1970-an sampai tahun 1990-an dengan berbagai istilah seperti kehutanan masyarakat (community forestry), pengelolaan hutan bersama (joint forest management) dan kehutanan sosial (social forestry). Berbagai kajian tentang PHBM dilakukan oleh banyak ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang memperkuat PHBM sebagai tata kelola hutan berkelanjutan. Wiersum (2004) menilai, pada awal abad ke-21, PHBM telah mencapai tingkat yang signifikan dan diterima sebagai strategi pengelolaan hutan yang berasal dari negara-negara tropis, dan kemudian PHBM juga berkembang di negara-negara yang lebih maju secara ekonomi seperti Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Meskipun demikian, kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap PHBM memang tidak tergambarkan secara jelas dalam peraturan kehutanan yang berlaku pada era orde baru (UU Nomor 5 Tahun 1967) dan era reformasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 6 Tahun 1967). Tabel 1 menyajikan jumlah istilah yang terkait dengan PHBM pada ketiga peraturan tersebut. Istilah-istilah pengelolaan hutan yang terkait dengan masyarakat masih didominasi oleh istilah masyarakat dan rakyat yang berdiri sendiri-sendiri. Pertimbangan masyarakat dan rakyat dalam peraturan tersebut juga lebih ditekankan sebagai objek dari kebijakan pembangunan kehutanan. Tabel 1. Kandungan Istilah-Istilah Terkait Dengan Pengelolaan Hutan Dan Masyarakat Istilah Jumlahnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 Jumlahnya dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Jumlahnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 268 Hutan 334 782 1,196 PHBM Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Perhutanan Sosial/Kehutanan Sosial Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Hutan Desa (HD) Tidak Ada 1 35 Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tidak Ada 2 37 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Tidak Ada Tidak Ada 38 Hutan Adat Tidak Ada 11 4 1 1 2 Tidak Ada 6 19 Masyarakat 18 129 101 Rakyat 23 25 4 Hutan Rakyat (HR) Pemberdayaan Tabel di atas juga memperlihatkan adanya ketimpangan pengaturan terkait skema HTR, HKm, dan HD dengan hutan adat sebagaimana terlihat pada PP Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong gugatan hukum (judicial review) AMAN kepada pemerintah terkait dengan komitmen mendukung hutan adat karena simbol yang dibangkitkan dari peraturan tersebut mengisyaratkan sebuah ketidakkonsistenan pemerintah. Akan tetapi sebenarnya, kebijakan dan strategi pengelolaan hutan nasional juga patut dipertanyakan karena peraturan-peraturan tersebut belum menggambarkan posisi yang jelas terhadap keberpihakan kepada masyarakat. Istilah PHBM dan perhutanan sosial/kehutanan sosial ternyata tidak dikenal dalam peraturan tersebut, tetapi dalam struktur organisasi Kementerian Kehutanan sejak 2006 sampai saat ini dipergunakan istilah perhutanan sosial. Penelitian ini menelusuri jejak istilah perhutanan sosial melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal yang membidangi perhutanan sosial untuk periode 2010-2014 dan 2015-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Masing-masing renstra tidak mendefinisikan istilah perhutanan sosial secara tegas, bahkan fokus program dan kegiatan perhutanan sosial tidak secara langsung dikaitkan sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria bidang kehutanan. Masalah-masalah agraria lebih dimaknai sebagai masalah tenurial sebagaimana diperkuat dalam Renstra Ditjen PSKL 2015-2019. Renstra ternyata tidak memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman rimbawan birokrat terhadap perhutanan sosial, kecuali sebatas program dan kegiatan dalam skema HTR, HKm, HD, Kemitraan, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Tabel 2. Fokus Perhutanan Sosial Dalam Rencana Strategis Fokus Pengertian definitif perhutanan sosial Renstra Ditjen RLPS 2010-2014 Tidak ada Renstra Ditjen PSKL 2015-2019 Tidak ada 269 Hubungan dengan Reforma Agraria Tidak ada Berkaitan dengan masalah tenurial Lingkup program dan kegiatan HKm, HD, dan Hutan Rakyat Kemitraan HTR,HKm, HD, Kemitraan, Hutan Rakyat, dan hutan adat Istilah perhutanan sosial menjadi sesuatu yang masih banyak tanda tanya karena ketidakjelasan definisi dan latar belakang penggunaan istilah tersebut dalam struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Bahkan dalam Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025, istilah ini juga tidak ditemukan. Satu-satunya penjelasan tentang perhutanan sosial termuat dalam bagian latar belakang renstra Ditjen PSKL 2015-2019 sebagai berikut: “Perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi se(r)ta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Demikian pula dalam penjelasan pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumberdaya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya” Penjelasan di atas mengklaim dasar perhutanan sosial sebagai representasi dari amanat UU Nomor 41 Tahun 1999 untuk pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada keadilan distribusi manfaat. Dalam konteks tersebut, perhutanan sosial sepertinya ditempatkan sebagaimana definisi reforma agraria yang dirumuskan oleh Soetarto dan Hermansah (2007) dan Suharjito (2013). Klaim HTR, HKm, dan HD sebagai kebijakan reforma agraria bidang kehutanan juga terlihat pada pokok-pokok bahasan Seminar Hasil Penelitian yang bertema “Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik” pada tanggal 7 April 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Perubahan Iklim (Puspijak) Kementerian Kehutanan. Perhutanan sosial telah menjadi simbol yang mengesankan adanya upaya reforma agraria bidang kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah. Simbol perhutanan sosial mampu membentuk persepsi publik bahwa pemerintah juga memperhatikan keinginan publik untuk menciptakan keadilan manfaat sumber daya hutan. Akan tetapi, akibat ketidakjelasan definisi dan kerangka konseptual perhutanan sosial, kebijakan pemerintah cenderung mendegradasi kekuatan simbol tersebut hanyalah sebagai program dan kegiatan, yang terikat pada skema-skema yang ditetapkan pemerintah. Merujuk pada definisi Wiersum (2004), perhutanan sosial seharusnya merupakan paradigma pembangunan kehutanan secara menyeluruh yang dijalankan oleh rimbawan dan organisasi lainnya untuk menstimulasi pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam skala kecil dengan beragam aktifitas pengelolaan hutan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Perhutanan sosial juga seharusnya dipandang sebagai strategi kunci dalam membangun tata kelola kehutanan yang lebih baik dan berlaku pada seluruh struktur organisasi kementerian yang berkaitan dengan pembangunan hutan dan kehutanan. Reforma agraria bidang kehutanan juga seharusnya dijalankan dengan pendekatan perhutanan sosial. Dalam kerangka strategi perhutanan sosial tersebut, ada 5 tahapan yang harus dikerjakan (Simon 2006), yaitu (1) 270 memahami karakter wilayah baik secara sosial budaya, ekonomi dan ekologis, (2) mengidentifikasi subsistem yang mempengaruhi sistem pembangunan wilayah, (3) melakukan kajian means and values, (4) menentukan tujuan pengelolaan, dan (5) menetapkan regime pengelolaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perhutanan sosial harus menjadi pelopor bagi penataan ruang wilayah dan lokal secara berkeadilan (Asmin 2016) yang juga menjadi fokus reforma agraria bidang kehutanan. 1.2. Pembelajaran Perhutanan Sosial dari Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat(Dishut Sumbar) memperlihatkan fenomena yang menarik dibahas terkait dengan perhutanan sosial. Sebenarnya, isu-isu keadilan manfaat sumber daya hutan juga dihadapi oleh rimbawan birokrat di Sumatera Barat sejak lama. Akan tetapi, isu degradasi hutan dan deforestasi lebih mengemuka dalam prioritas kebijakan kehutanan di Sumatera Barat. Kita mengenal kegiatan penghijauan dan reboisasi pinus sejak pertengahan tahun 1970-an, meskipun hasil dari kegiatan tersebut juga memunculkan masalah agraria pada awal tahun 2000-an. Penghijauan dan reboisasi oleh pemerintah kemudian dinilai oleh publik sebagai simbol penguasaan lahan oleh pemerintah. Pada awal tahun 2000-an tersebut, pemerintah juga sudah merintis pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) sebagai pilot proyek dengan menanam meranti pada beberapa lokasi. Kementerian Kehutanan selanjutnya membuat aturan-aturan baru terkait penetapan areal kerja HTR, HKm dan HD sejak tahun 2006 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang HTR, P.37/Menhut-II/2007 tentang HKm, dan P.49/Menhut-II/2008 tentang HD. Skema HTR merupakan skema pertama yang direspon oleh Dishut Sumbar sejak tahun 2007 dengan mendorong penetapan areal kerja HTR pada beberapa lokasi di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan. Skema HKm dan HD kemudian juga direspon sejak tahun 2010. Proses penetapan areal kerja dan perizinan juga membutuhkan waktu yang lama akibat birokrasi perizinan dari pusat yang cukup rumit. Menurut data tahun 2013, Dishut Sumbar telah mendorong pengusulan penetapan areal kerja HKm dan HD seluas 47,312 ha, namun realisasinya hanya 1,738 ha yang mendapatkan izin Menteri Kehutanan. Kerumitan birokrasi dalam perizinan HTR, HKm, dan HD ternyata tidak menyurutkan semangat Dishut Sumbar untuk mendorongnya. Dishut Sumbar membuat inovasi dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial pada tahun 2012 yang beranggotakan unsur dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keberadaan Pokja tersebut dimaksudkan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah mendorong perluasan skema-skema perhutanan sosial di Sumatera Barat. Dalam rencana kerjanya, Pokja mentargetkan areal hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat seluas 500,000 ha diarahkan untuk skema-skema perhutanan sosial seperti disajikan Tabel 3. Target tersebut ternyata menyumbangkan 20% dari target nasional saat itu. Tabel 3. Target Luasan Skema Perhutanan Sosial Di Sumatera Barat 271 No. Kabupaten/Kota 1. 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Sijunjung 5. Kabupaten Tanah Datar 6. Kabupaten Padang Pariaman 7. Kabupaten Agam 8. Kabupaten Lima Puluh Kota 9. Kabupaten Pasaman 10. Kabupaten Solok Selatan 11. 12. Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat 13. Kota Padang 14. Kota Sawahlunto JUMLAH Areal Potensial (Ha) Indikatif Lokasi (Kecamatan) 20.000 Kecamatan Siberut Selatan 37.500 Kecamatan Lunang Silaut, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, Koto XI Tarusan 60.000 Kecamatan Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Payung Sekaki, Tigo Lurah, Lembang Jaya, Gunung Talang, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, X Koto Di Atas, dan X Koto Singkarak 50.000 Kecamatan Kamang Baru, Tanjung Gadang, Sijunjung, IV Nagari, Koto VII, dan Sumpur Kudus 20.000 Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Tanjung Emas, Lintau Buo, Sungayang, Padang Ganting, dan Salimpaung 10.000 Kecamatan Lubuk Alung, VII Koto Sungai Sariak, dan V Koto Kampung Dalam 25.000 Kecamatan Lubuk Basung, Tilatang Kamang, Palembayan dan Palupuh 70.000 Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Harau, Suliki, Kapur IX, dan Pangkalan Koto Baru 71.000 Kecamatan Bonjol, Lubuk Sikaping, Duo Koto, Panti, Rao, Mapat Tunggul 50.000 Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuhan, dan Sangir Batanghari 25.000 Kecamatan Koto Baru dan Sitiung 46.500 Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Pasaman, Kinali dan Talamau 5.000 Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Pauh dan Koto Tangah 10.000 Kecamatan Lembah Segar, Barangin, dan Talawi 500.000 Sumber: Dishut Sumbar (2012) Perhutanan sosial juga menjadi basis bagi implementasi REDD+ (reducing emission from forest degradation and deforestation) di Sumatera Barat (Hermansah et al. 2013). Dishut Sumbar mampu mempengaruhi Satuan Tugas REDD+ Nasional yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto untuk mempertimbangkan Sumatera Barat sebagai provinsi percontohan implementasi REDD+ di Indonesia, padahal Sumatera Barat tidak termasuk dalam kategori provinsi dengan laju degradasi hutan dan deforestasi yang tinggi. Situasi ini kemudian membuat Sumatera Barat semakin “seksi” bagi LSM-LSM yang sedang mendorong reforma agraria seperti KKI Warsi, Qbar, Kemitraan, dan UNDP. Peran LSM dalam memperkuat posisi Dishut Sumbar untuk mendorong perhutanan sosial juga sangat penting, seperti yang dilakukan dalam mengembangkan kelembagaan hutan nagari di Jorong Simancuang Kabupaten Solok Selatan (Asmin 2015). Langkah Dishut Sumbar memang mampu mengkoordinasikan semua potensi untuk memperluas skema-skema perhutanan sosial. Akan tetapi, kerangka konseptual perhutanan sosial masih mengikuti kerangka konseptual nasional yang masih kurang jelas dan hanya dipahami sebatas program dan kegiatan semata. Jika kita melihat struktur organisasi Dishut Sumbar saat ini, perhutanan sosial dikelola oleh pejabat setingkat eselon IV (Kepala Seksi). 272 Perhutanan sosial sebenarnya juga kurang tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015 atau Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015.Alokasi sumber daya manusia (SDM) kehutanan juga menurun dari tahun ke tahun karena keterbatasan rekruitmen, sementara SDM yang tersedia untuk mendorong perluasan perhutanan sosial juga masih sedikit. Dishut Sumbar melihat potensi SDM yang dimiliki oleh LSM sangat besar untuk membantu program dan kegiatannya, termasuk dalam alokasi anggaran. Simbol perhutanan sosial dinilai efektif untuk mendorong semua pihak membantu program dan kegiatan Dishut Sumbar. Meskipun demikian, Dishut Sumbar perlu juga mempertimbangkan secara baik kebutuhan SDM di lingkungannya sendiri karena hanya sedikit rimbawan birokrat di Dishut Sumbar yang memahami perhutanan sosial. Kegagalan kebijakan pengembangan SDM kehutanan dapat menyebabkan program dan kegiatan yang dirintis menjadi kurang berarti, bahkan dinilai gagal. Upaya yang perlu didorong adalah menetapkan perhutanan sosial sebagai pendekatan utama pembangunan hutan dan kehutanan di Sumatera Barat. Setiap struktur dalam organisasi Dishut Sumbar didorong untuk menggunakan pendekatan ini dalam implementasi program dan kegiatannya. Hal ini tentunya diharapkan akan mendorong setiap individu rimbawan birokrat yang ada di Dishut Sumbar untuk mengimplementasikan perhutanan sosial dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan. Jadi, perhutanan sosial bukan semata dinilai sebagai program dan kegiatan sehingga harus ada struktur organisasi yang mengelolanya, tetapi perhutanan sosial harus menjadi cara berpikir seluruh rimbawan birokrat di Sumatera Barat. Dengan demikian, proses-proses deliberasi dalam pembangunan hutan dan kehutanan berjalan dalam kerangka perhutanan sosial dan memperkuat kebijakan reforma agraria bidang kehutanan itu sendiri di Sumatera Barat. 1.3. Peran Rimbawan Birokrat sebagaiWirausahawan Sosial Keberadaan hutan negara dapat menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, terutama bagi masyarakat terpencil sebagaimana diungkapkan oleh Tacconi dan Kurniawan (2006). Kompleksitas masalah kehutanan juga semakin besar ketika permasalahan-permasalahan hak ulayat menjadi persoalan struktural dalam reforma agraria di Indonesia. Di Sumatera Barat, Rajagukguk (2007) menyatakan bahwa penduduk setempat mengeluh terhadap kebijakan Pemerintah yang menafsirkan penguasaan atas tanah ulayat berarti penguasaan atas ”tanah negara”. Persoalan tanah ulayat ini juga menjadi salah satu dasarjudicial review dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap pengertian hutan adat pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam amar putusannya nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “negara” dalam pengertian hutan adat sehingga hutan adat bukan lagi termasuk kategori hutan negara. Persoalan konsepsi agraria yang dijalankan pemerintah juga masih dipersepsikan lebih menggunakan pendekatan kepentingan usaha dan investasi karena pemerintah cenderung membuka kesempatan kepada penanam modal perusahaan swasta dalam dan luar negeri (Rajagukguk 2007). Pada sisi yang lain, implementasi program dan kegiatan perhutanan sosial juga tidak semakin mudah. Hal ini terjadi karena pemerintah cenderung memaksakan skema tanpa memperhatikan dukungan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Pola perencanaan dan kelembagaan juga lebih cenderung bersifat top down, sehingga dikhawatirkan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Sangat memungkinkan dengan cara-cara seperti itu menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan berpotensi mengkerdilkan semangat reforma agraria 273 dalam konteks penyelesaian masalah tenurial dan konflik sosial. Ketika strategi perhutanan sosial menjadi prioritas dalam pengelolaan hutan nasional dan daerah, maka kelembagaan lokal yang seharusnya dibangun adalah kelembagaan partisipatif (participatory institutions), bukan kelembagaan publik (public institutions) dan privat (private institutions). Ciri kelembagaan partisipatif adalah membantu anggota masyarakat dengan kekuatan yang dimilikinya (self-help) dan dapat melayani kepentingan-kepentingan publik dan privat (Uphoff 1986). Akan tetapi, melihat ciri kelembagaan dalam HKm, HD, HTR, dan HR sebagai bagian dari program perhutanan sosial, pemerintah cenderung memilih kelembagaan publik atau privat dengan bergaya birokratis, politis, dan orientasi keuntungan finansial (Asmin 2016). Berdasarkan hal tersebut di atas, kapasitas rimbawan birokrat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan dan reforma agraria bidang kehutanan perlu diperkuat. Cara berpikir dan bertindak seorang rimbawan birokrat bukan lagi menyelesaikan masalah tenurial dengan berbagai inisiasi program dan kegiatan, tetapi seharusnya bagaimana membangkitkan dan mensinkronkan semangat reforma agraria di pemerintahan dan masyarakat. Dengan kondisi sosial politik seperti saat ini, maka seorang rimbawan harusnya menjadi seorang wirausahawan sosial (social entrepreneurs) untuk mampu menginternalisasikan semangat reforma agraria di tubuh birokrasi.Bornstein dalam Rogers et al. (2008) menjelaskan bahwa ada 6 kualitas untuk menjadi social entrepreneurs yang berhasil adalah: (1) keinginan untuk koreksi diri, (2) keinginan untuk berbagi peran, (3) keinginan untuk memecahkan struktur terbangun, (4) keinginan untuk mempelajari multi disiplin ilmu, (5) keinginan untuk bekerja baik, dan (6) memiliki etika yang kuat. Ide rimbawan birokrat sebagai wirausahawan sosial berangkat dari pentingnya ilmuilmu sosial dalam pengembangan ilmu pengetahuan kehutanan. Salah satu kegagalan ilmu pengetahuan kehutanan selama ini adalah ketidakmampuan ilmu pengetahuan kehutanan merekayasa dinamika sosial dalam desain pengelolaan hutan. Rekayasa kehutanan selama ini lebih cenderung berorientasi pada ekologis dan ekonomi. Social engineering belum terelaborasi lebih detail dalam program dan kegiatan sektor kehutanan karena kapasitas sosial rimbawan birokrat masih belum memadai.Yang paling mengkhawatirkan adalah rimbawan birokrat cenderung mengabaikan dinamika sosial dan menganggap permasalahan sosial (seperti masalah tenurial) hanya sebagai bagian dari rekayasa politik segelintir orang yang berkepentingan terhadap hutan dan hasil hutan. Hal ini menyebabkan desain politik kehutanan cenderung berkaitan dengan masalah-masalah penegakan hukum. Politik kehutanan mengarah pada politik feodalisme yang menganggap tanah sebagai aset sumber daya bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesederhanaan berpolitik tersebut membawa rimbawan birokrat sebagai objek politik negara dalam melestarikan kekuasaan. Bagaimana mungkin reforma agraria bidang kehutanan berjalan dengan baik bila rimbawan birokratnya memiliki visi sosial dan politik yang lemah. Dengan mendorong rimbawan birokrat menjadi wirausahawan sosial, kita mengharapkan pembangunan hutan dan kehutanan yang berkeadilan dapat tercapai. 5. KESIMPULAN Perhutanan sosial merupakan simbol reforma agraria bidang kehutanan yang mampu membangun persepsi publik bahwa pemerintah telah dan sedang menjalankan agenda reforma agraria bidang kehutanan. Skema perhutanan sosial yang menjadi bagian dari kebijakan reforma agraria bidang kehutanan adalah HTR, HKm, HD, Kemitraan, dan Hutan Adat. Meskipun ada ketidakjelasan kerangka konseptual perhutanan sosial, baik di pusat dan daerah, perhutanan sosial mendapatkan perhatian yang luas dari berbagai LSM 274 yang selama ini menyuarakan gerakan-gerakan reforma agraria bidang kehutanan, seperti yang terjadi di Sumatera Barat.Dalam konteks politik simbolik, simbol perhutanan sosial memang menjadi alat yang efektif untuk membangun komunikasi baru dalam menjalankan reforma agraria bidang kehutanan. Namun demikian, ketidakjelasan kerangka konseptual perhutanan sosial mendegradasi perhutanan sosial dalam kerangka program dan kegiatan semata sebagaimana yang diyakini oleh rimbawan birokrat pusat dan daerah. Hal inilah yang menyebabkan implementasi skema-skema perhutanan sosial masih sangat rendah. Penelitian ini mendorong perhutanan sosial sebagai kebijakan dan strategi nasional dan daerah yang berlaku dalam setiap program dan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan. Artinya, perhutanan sosial seharusnya ditempatkan sebagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan hutan dan kehutanan untuk menjaminkonsistensi kebijakan reforma agraria bidang kehutanan menuju tata kelola kehutanan yang lebih baik. Dengan demikian, proses-proses deliberasi dalam paradigma perhutanan sosial dapat dijalankan oleh seluruh rimbawan birokrat dalam berbagai struktur dan tingkatan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik di pusat dan daerah. Di samping itu, kebijakan dan strategi perhutanan sosial sebagai pendekatan pembangunan hutan dan kehutanan juga harus diikuti dengan penguatan kapasitas rimbawan birokrat menuju kualitas wirausahawan sosial yang mampu menginternalisasikan semangat reforma agraria bidang kehutanan pada tingkat masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian, simbol perhutanan sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap jaminan keadilan manfaat sumber daya hutan di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini perlu dilengkapi dengan kajian politik simbolik yang dijalankan oleh LSM sebagai penggerak utama semangat reforma agraria bidang kehutanan. LSM dapat dinilai sebagai salah satu rimbawan yang berjuang di luar birokrasi pemerintahan dan strategi LSM juga mengandung simbol-simbol yang mempengaruhi politik agraria bidang kehutanan di Indonesia. Hal ini merupakan tantangan penelitian selanjutnya yang menarik dilakukan. 6. DAFTAR PUSTAKA Asmin, Ferdinal. 2015. Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat: Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simancuang Provinsi Sumatera Barat. Disampaikan pada Seminar Nasional FMIPA UT Tahun 2015 pada tanggal 22 Oktober 2015 di Jakarta, Indonesia. Asmin, Ferdinal. 2016. Elaborating the Attributes of Local Ecological Knowledge: A Case Study of Parak and Rimbo Practices in Koto Malintang Village. Disampaikan pada International Conference on Social Sciences and Humanities pada tanggal 19-21 April 2016 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Barber, Charles Viktor. 1998. Forest Resource Scarcity and Social Conflict in Indonesia. Environment 40(4):4-9. Berg,Bruce Lawrence. 2001. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. New York: A Pearson Education Company. Bernstein, Steven, Benjamin Cashore, Richard Eba’a Atyi, Ahmad Maryudi, dan Kathleen McGinley. 2010. Examination of the Influences of Global Forest Governance Arrangements at the Domestic Level. IUFRO World Series 28:111-135. Blühdorn, Ingolfur. 2007. Sustaining the Unsustainable: Symbolic Politics and the Politics of Simulation. Environmental Politics 16(2):251-275. Charnley, Susan dan Melissa R. Poe. 2007. Community Forestry in Theory and Practice: Where are We Now? Annu. Rev. Anthropol 36:301–336. 275 Daryanto, Hadi. 2014. Sekelumit Permasalahan Mendasar dalam Reforma Agraria dan Tata Kelola Hutan di Indonesia. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jakarta: Kementerian Kehutanan. [Dishut Sumbar] Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 2012. Rencana Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat Periode 2012-2017. Padang: Dishut Sumbar. Edelman, Murray. 1971. Politics as Symbolic Action: Mass Arousal and Quiescence. New York: Academic Press, Inc. Edelman, Murray. 1977. Political Language: Words that Succeed and Policies that Fail. New York: Academic Press, Inc. Edelman, Murray. 2001. The Politics of Misinformation. Cambridge: Cambridge University Press. [FWI] Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. Jakarta: FWI. Guiang, Ernesto S., Salve B. Borlagdan, dan Juan M. Pulhin. 2001. Community-Based Forest Management in the Philippines: A Preliminary Assessment. Manila: Institute of Philippine Culture, Ateneo De Manila University. Hermansah, Gemala Ranti, Siti Aisyah, Jusmalinda, Ferdinal Asmin, Vonny Indah Mutiara, Rainal Daus, dan Agus W. Boyce. 2013. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Implementasi REDD+. Padang: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Tugas REDD+ Indonesia. [KemenLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014. Jakarta: KemenLHK. [KPA] Konsorsium Pembaharuan Agraria. 2016. Catatan Akhir Tahun 2015: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi. Jakarta: KPA. Maryudi, Ahmad dan Max Krott. 2012. Local Struggle for Accessing State Forest Property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia. Journal of Sustainable Development 5(7):62-68. Matten, Dirk. 2003. Symbolic Politics in Environmental Regulation: Corporate Strategic Responses. Business Strategy and the Environment 12:215–226. Molnar, Augusta, Marina France,Lopaka Purdy, dan Jonathan Karver. 2011. CommunityBased Forest Management: The Extent and Potential Scope of Community and Smallholder Forest Management and Enterprises. Washington: The Rights and Resources Initiative (RRI). Newig, Jens. 2007. Symbolic Environmental Legislation and Societal Self-Deception. Environmental Politics 16(2):276–296. Niemeyer, Simon. 2004. Deliberation in the Wilderness: Displacing Symbolic Politics. Environmental Politics 13(2):347 – 372. Poffenberger, Mark. 2006. People in the Forest: Community Forestry Experiences from Southeast Asia. Int. J. Environment and Sustainable Development 5(1):57–69. Rajagukguk, Erman. 2007. Indonesia Setelah Merdeka: Menyusun Hukum Tanah untuk Rakyat. Makalah Seminar Antarbangsa, “Tanah Keterhakisan Sosial dan Ekologi : Pengalaman Malaysia dan Indonesia”, Dewan Bahasa dan Pustaka Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur, 4-5 Desember 2007. Rogers, Peter P., Kazi F. Jalal, dan John A. Boyd. 2008. An Introduction to Sustainable Development. London: Glen Educational Foundation, Inc. 276 Sam, Thida. 2011. Community Forest Management. United Nations Forum on Forests, UNFF9: “Forests for People, Livelihoods and Poverty Eradication” di New York City pada tanggal 24 Januari sampai 4 Februari 2011. Sardjono, Mustofa Agung. 2013. Membawa Perhutanan Sosial Indonesia ke Upaya yang Lebih Menjanjikan. Di dalam: Kartodihardjo, Hariadi (editor). Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta: Nailil Printika. pp. 397-422. Simon, Hasanu. 2006. Hutan Jati dan Kemakmuran: Problematika dan Strategi Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soetarto, Endriatmo dan Tantan Hermansah. 2007. Ekonomi Pedesaan, Dinamika Sumber Daya Alam dalam Pandangan Reforma Agraria di Indonesia. Makalah pada Konpernas PERHEPI. Tanggal 3-5 Agustus 2007, di Hotel Sahid Raya, Solo. Stan, Lavinia. 2010. Content Analysis. Di dalam: Mills, Albert J., Gabrielle Durepos, dan Elden Wiebe (editor). Encyclopedia of Case Study Research. California: SAGE Publications, Inc. pp. 225-229. Suharjito, Didik. 2013. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial, dan Kemakmuran Bangsa. Di dalam: Kartodihardjo, Hariadi (editor). Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta: Nailil Printika. pp. 423450. Suharjito, Didik. 2014. Pengantar Metodologi Penelitian. Bogor: PT Penerbit IPB Press. Tacconi, Luca dan Iwan Kurniawan. 2006. Forests, Agriculture, Poverty and Land Reform: The Case of the Indonesian Outer Islands. Canberra: Australian National University. Teitelbaum, Sara. 2014. Criteria and Indicators for the Assessment of Community Forestry Outcomes: A Comparative Analysis from Canada. Journal of Environmental Management 132:257-267. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31 31:1-14. Wiersum, K. Freerk. 2004. Social and Community Forestry. Di dalam: Burley, Jeffery, Julian Evans, dan John A. Youngquist (editor). Encyclopedia of Forest Sciences. Oxford: Elsevier Ltd. pp. 1136-1143. KERAWANAN KONFLIK SOSIAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT Dr. Herlan, S.Sos, M.Si Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungura) Email: [email protected] Abstrak Indonesia menjadi salah satu negara terbesar pengekspor CPO dunia dan memiliki areal kelapa sawit selama 2004 - 2014 seluas 10.956.231 ha dengan produksi kelapa sawit meningkat rata-rata 11,09% per tahun. Seiring dengan semakin meluasnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah memunculkankerentanan 277 konfliksosial dalamberbagaiwujud. Salah satunya yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini yaitukerawanan konflik sosial di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang memiliki areal perkebunan seluas 2.050.152 ha, dengan jumlah perusahaan yang mengelola sebanyak 428 buah. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: “faktor-faktor apa saja penyebab pembangunan perkebunan kelapa sawit tetap rawan konflik sosial di provinsi Kalimantan Barat ? Hasil penelitian terungkap bahwa bentuk-bentuk konflik sosial atas pembangunan perkebunan kelapa sawit, antara lain: (1) demonstrasi kepada Pemerintah Daerah (Bupati / DPRD); (2) pemagaran lahan perkebunan milik perusahaan; (3) Penyitaan / Penyegelan Barang atau Mesin; (4) Pemukulan, penganiayaan dan Pembakaran, dan (5) Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada pihak Perusahaan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya kerentanan konflik sosial, yaitu: (1) sengketa lahan, (2) lemahnya keadilan dan penegakan hukum, (3) perusahaan mengabaikan kepentingan masyarakat dan (4) arogansi pihak perusahaan dalam menjalan aktivitas usaha. Kata Kunci: Kerawanan, Konflik Sosial, Perkebunan Abstract Indonesia is the country of the biggest CPO exporter around the world. During 2004 to 2014, the average growth rate of oil palm plantation area and one of production of FFB is 7,67% and 11,09 %, respectively.In 2014, the area of oil palm plantation reached 10.9 million ha and the production of CPO reached 29,3 million tons.Smallholder: 4,55 million ha (41,55% in total)National company (PTPN): 0.75 million ha (6.83 %in total)Private company: 5,66 million ha (51.62 % in total). Foreign private company: 0,17 million ha (1.54 % in total). Oil palm plantation development has created vulnerability social conflict in various form, among other. Between the community with private or national company and among communities.West Kalimantan province have experienced sever social conflict caused by oil palm plantation development.This presentation focus on the case study of West Kalimantan.The theme of this presentation is to clarify the factors promoting oil palm plantation development that make social conflicts in West Kalimantan province. The research as forms of social conflict over development palm oil plantation, among others: (1) demonstration to local government (regent parliament to demand compensation of not denying the presence of oil palm plantation); (2) the restoration of company-owned plantations; (3) seizure/sealing goods or amachine; (4) the beating of, persecution and burning, and (5) customary sanctions to the company.Vulnerability of social unrest of oil palm plantations in West Kalimantan can be divided into several factors; (1) land conflict disputes, (2) the weak justice and law enforcement, (3) the company ignoring public interests and (4) arrogance of the company in executing business activity. Keyword: Social Conflict, Palm Oil Plantation. 1. PENDAHULUAN Indonesia dewasa ini telah menjadi salah satu negara terbesar pengekspor CPO dunia hal ini seiring dengan semakin gencarnya program pengembangan komoditas kelapa sawit dari tahun ke tahun, terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit selama 2004 - 2014 sebesar 7,67%, sedangkan produksi kelapa sawit meningkat rata-rata 11,09% per tahun. Hal ini disebabkan antara lain perkebunan kelapa sawit dirasakan memberikan manfaat positif pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sawit. Berdasarkan buku statistik komoditas kelapa sawit terbitan Ditjen Perkebunan, pada Tahun 2014 luas areal kelapa sawit mencapai 10,9 juta Ha dengan produksi 29,3 juta ton CPO. 278 Luas areal menurut status pengusahaannya milik rakyat (Perkebunan Rakyat) seluas 4,55 juta Ha atau 41,55% dari total luas areal, milik negara (PTPN) seluas 0,75 juta Ha atau 6,83% dari total luas areal, milik swasta seluas 5,66 juta Ha atau 51,62%, swasta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu swasta asing seluas 0,17 juta Ha atau 1,54% dan sisanya lokal. Tanaman kelapa sawit saat ini tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Riau pada Tahun 2014 dengan luas areal seluas 2,30 juta Ha merupakan provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas disusul berturut-turut Provinsi Sumatera Utara seluas 1,39 juta Ha, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1,16 juta Ha dan Sumatera Selatan dengan luas 1,11 juta Ha, Kalimantan Barat seluas 959,226 ha. serta provinsiprovinsi lainnya. Tabel 1. Sebaran Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2014 No. Provinsi Luas Produksi 1. Riau 2.296.849 7.037.636 2. Sumatera Utara 1.392.532 4.753.488 3. Kalimantan Tengah 1.156.653 3.312.408 4. Sumatera Selatan 1.111.050 2.852.988 5. Kalimantan Barat 959.226 1.898.871 6. Kalimantan Timur 856.091 1.599.895 7. Jambi 688.810 1.857.260 8. Kalimantan Selatan 499.873 1.316.224 9. Aceh 413.873 853.855 10. Sumatra Barat 381.754 1.082.823 11. Bengkulu 304.339 833.410 12 Kep. Bangka Belitung 211.237 538.724 13 Lampung 165.251 447.978 14 Sulawesi Tengah 147.757 259.361 15 Sulawesi Barat 101.001 300.396 Jumlah 10.956.231 29.344.479 Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Nopember 2014 Seiring dengan semakin meluasnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah memunculkankerentanan konfliksosial dalamberbagaiwujud,antaralain: masyarakat dengan badan-badan usaha baik milik negara maupun swasta, maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Situasi tersebut dapat dijelaskan secara teori maupun kenyataan dilapangan. Secara teoritis, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan tanah dalam skala mega hektar sebagai faktor produksi utama,sementara disisi lain apa yang disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara tidaklah sebanyak tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat baik berupa tanah tanah adat maupun hak milik. Kenyataan inilah yang menyebabkan tanahtanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat pun diincar untuk dijadikan lahan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam situasi itulah konflik-konflik itu bermula yang kemudian berkembang dengan varian-varian sebab, akibat, maupun dampaknya. Salah satu wilayah yang mengalami kerentanan konflik sosial dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini yaituwilayah provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu fokus permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: “faktor-faktor apa saja penyebab pembangunan perkebunan kelapa sawit tetap rawan konflik sosial di provinsi Kalimantan Barat ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam proses pengambilan data dilakukan dengan 4 (empat) teknik, yaitu (1) Desk Research; (2) Focus Group Discusion 279 (FGD); (3) One to One in-depth interview; dan (4) Observasi, lokasi penelitian pada 13 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat, yang selama ini telah dilaksanakannya pembangunan perkebunan kelapa sawit. I. Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat Wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari 35 provinsi di Indonesia, apabila dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk propinsi keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km²), kedua Kalimantan Timur (202.440 km²) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km²). Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Arah kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mengadopsi arah kebijakan dari program pemerintah Pusat, yaitu pengembangan agrobisnis kebun, pengembangan sistem informasi dan pemberdayaan kelembagaan perkebunan. Oleh sebab itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat juga merencanakan ekspansi perkebunan sawit secara besar-besaran.Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan tahun 2014 daftar perijinan yang sudah masuk sebanyak 2.050.152 ha, dengan jumlah perusahaan yang mengelola sebanyak 428 buah. Tabel 2. Daftar Perijinan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Luas Areal Luas Kalbar Jumlah No. Kabupaten Perkebunan (Km2) Perusahaan Kelapa Sawit (Ha) 1 Sambas 6.394,70 155.870 40 2 Mempawah 1.276,90 52.079 9 3 Kubu Raya 6.985,20 155.320 32 4 Singkawang 504,00 19.993 1 5 Bengkayang 5.397,30 130.821 43 6 Landak 9.909,10 182.850 54 7 Sanggau 12.857,70 349.198 48 8 Sekadau 5.444,30 136.744 22 9 Sintang 21.635,00 227.128 47 10 Melawi 10.644,00 72.740 16 11 Kapuas Hulu 29.842,00 124.564 29 12 Ketapang 31.240,74 396.421 81 13 Kayong Utara 4.568,26 46.424 6 14 Kota Pontianak 107,80 0 0 Jumlah 146.807,00 2.050.152 428 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2015 Pembangunan perkebunan di Kalimantan Barat, termasuk kelapa sawit, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, 280 menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku dalam negeri, mendorong pengembangan wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelapa sawit merupakan tanaman daerah tropis yang membutuhkan curah hujan yang cukup. Bagi Indonesia pada umumnya, selain kesesuaian agroklimat tanaman ini juga mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dan biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lain seperti minyak kedelai, rape seed maupun bunga matahari. Pengembangan kelapa sawit yang dilakukan di Kalimantan Barat dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengembangan kelapa sawit.Sebagai Guidance untuk melaksanakan dan melakukan penilaian tentang pembangunan kelapa sawit di Indonesia disusun Sistem Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesia Sustainable Palm Oil-ISPO.Tujuan ditetapkannya ISPO adalah : 1) 2) 3) Meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan, Meningkatkan tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, dan Mendukung komitmen Indonesia dalam pertemuan Copenhagen 2009. Karena ISPO didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan ini merupakan mandatory/kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia. Berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang merupakan landasan dalam penerapanSistem Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ) antara lain: 1) Undang-undang No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, 2) Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 3) Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 4) Undang-undang No.41 tahun 2000 tentang Kehutanan, 5) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah, 6) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, 7) Permentan No.26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, 8) Permentan No.14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, 9) Permentan No.7 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, 10) Permentan No.36 tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan, 11) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, 12) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts-II/1990, 519/Kpts/Hk.050/7/1990 dan 23/VIII/90 dan 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan, 13) Peraturan Dirjenbun No.174 tahun 2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional, 281 Hasil dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat diakui memang telah memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pemenuhan kebutuhan pangan dan nonpangan dan ekspor yang mendatangkan devisa bagi negara. Susila (2004) mengutip hasil penelitian Asian Development Bank (ADB, 2002) menunjukkan bahwa nilai koefisien gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan di wilayah perkebunan sawit relatif baik dengan koefisien 0,36. Nilai tersebut termasuk kategori pendapatan yang relatif merata, karena masih di bawah 0,40 sebagai ambang dari mulai ada indikasi ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang cukup baik. Jumlah rumah tangga yang pendapatannya sekitar Rp 5 juta yang termasuk katagori miskin relatif kecil. Pendapatan rumah tangga secara umum di atas Rp 10 juta-Rp 25 juta per tahun, yang jauh di atas garis kemiskinan. Proporsi masyarakat ini mencapai di atas 75% dari total rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa perkebunan sawit berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan. II. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), ditinjau dari pengelompokkan penduduk tergolong majemuk dan sering terjadi konflik sosial antar etnik khususnya antara etnik Dayak dan etnik Madura, sehingga Kalbar dikenal sebagai daerah rawan konflik. Arafat (1998) mencatat bahwa sejak 1933 sampai dengan 1977, telah terjadi 10 kali konflik dengan kekerasan. Menurut Petebang, et al (2000) sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1999 telah terjadi sebanyak 12 kali, dan Alqadrie (2002) mengungkapkan konflik kekerasan antar etnik di Kalbar terjadi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Sebanyak 10 (sepuluh) kali melibatkan kelompok etnik Dayak dengan kelompok etnik Madura, yakni pada tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1977, 1979, 1983, 1996, 1997 dan 1999. Sebanyak 1 (satu) kali antara kelompok etnik Dayak dengan kelompok Tionghoa, yakni tahun 1967. Kemudian 2 (dua) kali antara kelompok etnik Melayu dengan etnik Madura, tahun 1999 dan 2000. Kerawanan potensi konflik di Kalimantan Barat sekarang ini tidak lagi hanya ditinjau dari perbedaan etnik semata tetapi lebih cenderung dan lebih menonjol pada konflik pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu antara (1) Kelompok-kelompok yang berkonflik itu masyarakat adat dengan perkebunan, (2) karyawan dengan perusahaan, (3) pemilik lahan dengan pemerintah. Selain itu, juga (4) masyarakat dengan pemerintah, (5) perusahaan dengan pemerintah, (6) masyarakat dengan masyarakat, (7) masyarakat dengan LSM dan (8) LSM dengan pihak perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dan pemberitan media massa, terungkap bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan Desember 2011 terdapat perbandingan jumlah kasus konflik perkebunan di Kalimantan Barat. (lihat tabel 3). Jumlah konflik adalah angka tercatat berdasarkan amatan maupun investigasi lembaga pencatat. Oleh karena itu selalu ada ”the dark number” yang merupakan konflikkonflik yang tidak teramati atau terinvestigasi sehingga tidak nampak dalam database. Dengan begitu, jumlah konflik perkebunan kelapa sawit yang sebenarnya akan lebih banyak dari jumlah 116 kasus. Tabel 3.Data Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat Kesbangpol Tim Peneliti No Kabupaten / Kota Kasus Tahun Kasus Tahun Kasus Tahun 2009 s/d 2011 2012 2013 1 Kab Kubu Raya 22 0 0 2 Kab Sanggau 15 5 0 3 Kab Sintang 17 6 6 282 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kab Ketapang 10 Kab Sambas 13 Kab Sekadau 10 Kab Kapuas Hulu 7 Kab Landak 6 Kab Mempawah 3 Kab Melawi 3 Kab Bengkayang 5 Kab Kayong Utara 1 Kota Singkawang 4 Kota Pontianak 0 Jumlah 116 Sumber: Data Diolah, Tim Peneliti 2015 5 3 1 3 0 0 4 4 1 0 0 32 5 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 18 Adapun bentuk-bentuk konflik sosial atas pembangunan perkebunan kelapa sawit, antara lain: 1. Demonstrasi Kepada Pemerintah Daerah (Bupati/DPRD) untuk menuntut ganti rugi maupun menolak kehadiran perkebunan Kelapa Sawit Peristiwa demonstrasi ke kantor Bupati maupun DPRD Kabupaten hampir pernah terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan tuntutan berupa masalah tapal batas, pengambilalihan lahan, ganti rugi lahan, investasi. Contoh kasus: a) Konflik lahan (ganti rugi lahan dan sanksi adat) antar masyarakat Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak dengan pihak perusahaan PT SAM (Sintang Agro Mandiri), dengan eskalasi konflik pengerahan massa demo (unjuk rasa) dan pengrusakan kantor perusahaan pada tanggal 26 Februari 2011. b) Konflik antar warga Dusun Engkeruh Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu dengan Perusahaan DAP (Duta Agro Prima) dengan eskalasi konflik berupa sikap menolak keberadaan perusahaan di wilayah tersebut. c) Konflik antar warga masyarakat Dusun Mengsuang Kecamatan Ambalau dan Dusun Gurung Permai Desa Gurung Sengiang Kecamatan Serawai dengan pihak PT SSA (Sinar Sawit Andalan) dan PT SHP (Sumber Hasil Prima) di Kecamatan Ambalau pada tanggal 3 Mei 2012, dengan eskalasi konflik unjuk rasa menolak keberadaan perusahaan di daerah tersebut. 2. Pemagaran Kebun Perusahaan oleh WargaSekitar. Contoh kasus seperti: a. Konflik antar warga masyarakat Dusun Landung dan Dait dengan perusahaan PTPN XIII Nanga Jetak, dengan eskalasi konflik pemagaran lahan perkebunan oleh masyarakat (Polres Sintang, 08/10/2013) b. Konflik antar warga Dusun Begendang Desa Natai Panjang Kecamatan Kayan Hilir dengan PT BSL (Bumi Sentosa Lestari), dengan eskalasi konflik pengerahan masa dan pemagaran areal perusahaan pada tanggal 1 Februari 2012 (Sumber: Polres, 08/10/13). c. Konflik antar warga masyarakat Desa Sei. Risap Kecamatan Binjai Hulu dengan PT SNIP (Satya Nusa Indah Perkasa) pada tanggal 02 April 2012 dengan eskalasi konflik berupa pemagaran/penutupan akses 3. Penyitaan / Penyegelan Barang atau Mesin Milik Perusahaan, contoh kasus seperti: a. Konflik lahan antara warga masyarakat Desa Tanjung Prada Kecamatan Tempunak dengan pihak PT SAM pada tanggal 12 Desember 2012, dengan 283 eskalasi konflik penahanan 3 kunci kendaraan berat milik perusahaan oleh warga. b. Konflik Lahan Perkebunan antara Masyarakat Desa Balai Gemuruh Dengan PT. KSUP (Karya Sukses Utama) pada tanggal 18 mei 2013, warga melakukan penahanan terhadap 3 buah alat berat jenis buldozer milik PT. KSUP. 4. Pemukulan, penganiayaan dan Pembakaran, contoh kasus seperti: a) Konflik antar warga Dusun Beringin Jaya Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai dengan Satgas perkebunan PTPN XIII, dengan eskalasi konflik pemukulan, pembakaran kendaraan bermotor dan pengrusakan pos Satgas (Equator, 22/09/08) dan (Pontianak Post, 23/09/08) b) Konflik antar warga masyarakat Desa Lebak Ubah, Bloyang, Melayang Sari dan Panjernang Kecamatan Sei. Tebelian dengan pihak PT SDK IV (Sinar Dinamika Kapuas 4) pada tanggal 9 Maret 2011, dengan eskalasi konflik pengerahan masa dan pembakaran kamp. perusahaan oleh warga (sumber: Polres, 08/10/13). 5. Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada pihak Perusahaan, contoh kasus : a. Konflik antara warga Dusun Kancing II dan Desa Sepak Tonak Kecamatan Belimbing kabupaten Melawi dengan PT Rafi Kama Jaya, dengan eskalasi tuntutan melakukan prosesi adat dalam melakukan penebangan oleh perusahaan., tahun 2012. III. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Perkebunan 1. Sengketa Lahan Sengketa lahan adalah faktor utama penyebab konflik perkebunan yang sering mengemuka di masyarakat. Tak heran masyarakat yang selalu menjadi korban ketidakadilan. Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan persoalan tanah. Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat, terutama masyarakat adat. Lebihlebih, masyarakat adat bukan hanya meyakini dirinya sebagai penguasa tanah, tetapi sebagai pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari, sehingga cukup kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya. Namun, karena aturan dan kebijakan pemerintah mengatakan sebaliknya, bahwa pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah untuk dan demi kepentingan nasional, tanah-tanah yang dipertahankan oleh masyarakat itu, dicarikan ’jalan’ melalui sejumlah peraturan dan kebijakan, Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan persoalan lahan (tanah).Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat, terutama masyarakat adat. Lebihlebih, masyarakat adat bukan hanya meyakini dirinya sebagai penguasa tanah, tetapi sebagai pemilik tanah atas dasar hukum adat yang mereka jalankan sehari-hari, sehingga cukup kuat untuk dipertahankan kepenguasaan dan atau kepemilikannya. Namun, karena aturan dan kebijakan pemerintah mengatakan sebaliknya, bahwa pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah untuk dan demi kepentingan nasional, tanah-tanahyang dipertahankan oleh masyarakat itu,dicarikan ’jalan’ melalui sejumlah peraturan dan 284 kebijakan, agarbisa diambil alih untuk pembangunan kebun sawit. Akibatnya, banyak tanah-tanah dalam penguasaan dan atau pemilikan masyarakat yang diambil alih baik melalui cara-cara kekerasan maupun dengan tipu daya informasi. Berbagai skema kerja sama pun dirumuskan untuk memudahkan proses pengambi-alihan tanah dari masyarakat, antara lain skema inti-plasma, koperasi, jual beli, konsolidasi tanah maupun kompensasi. 2. Lemahnya Keadilan dan Penegakan Hukum Lemahnya keadilan disini terlihat dari adanya penyerangan dan penangkapan terhadap warga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah. Seperti kasus di Kabupaten Sambas, pada bulan November 2001, 50 anggota Brimob (Indonesia police special force) menyerang warga Dayak Bakati' dan menangkap sejumlah tokoh adat yang menolak masuknya perkebunan kelapa sawit PT. RWK di sana. Meski didemo ratusan warga Dayak, tokoh adat ini ditangkap, diadili dan dipenjara dua tahun."Selama ini, banyak perusahaan perkebunan sawit meminta pengamanan kepada pihak kepolisian. Padahal, tugas Polisi adalah menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat Kalbar,". Oleh sebab itu rasa keadilan kurang mendapat perhatian terkait adanya keberfihakan pihak kepolisian pada pihak perusahaan. Adanya indikasi ketimpangan kebijakan dan kepemihakan keadilan dalam penegakan hukum adalah penyebab utama permasalahan, bila tidak ditangani secara konsisten maka konflik akan terus-menerus terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti (2015), terungkap bahwa, seluruh wilayah di Kalimantan Barat dimana terdapat perkebunan kelapa sawit (11 Kabupaten dan 1 kota) mengalami konflik sengketa lahan. Sengketa lahan terjadi antara (1) pihak perusahaan dengan tanah masyarakat setempat dan tanah adat, (2) Sengketa tapal batas antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten). Lemahnya Penegakan hukum dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit ternyata tidak sedikit perusahaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi berbagai syarat dan kewajiban hokum sesuai aturan yang berlaku. Meskipun begitu, sebagian besar telah melakukan serangkaian tindakan operasional dalam rangka pembangunan perkebunan sawit. Misalnya, Hak Guna Usaha(HGU) baru dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit setelah kebun sawit dioperasikan bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya bermodal Izin Lokasi dalam membangun kebunnya.Disampingitu,tidaksedikit perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan pada saat pemberian Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN). Menurut hokum dengan logika penalarannya yang positif, perusahaan-perusahaan yang demikian terbilang tidak memiliki keabsahan hokum untuk melakukan tindakantindakan hokum seperti mengoperasionalkan perkebunan sawit sebelum dipenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Karena, sebagaimana diketahui dalam setiap SKHGU adalah usul yang menyatakan bahwa apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi, maka SKHGU batal dengan sendirinya. Jika SKHGU tersebut secara hokum batal, maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demihukum, karena sudah tidak ada lagi alashak yang menjadi dasar hokum pengoperasian perusahaan. Namun pada kenyataannya dilapangan, perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tetap menjalankan operasi perkebunan. 3. Perusahaan Mengabaikan Kepentingan Masyarakat Perusahaan yang hanya mementingkan pengembangan perusahaan semata dengan mengorbankan kepentingan masyarakat adalah penyebab konflik lainnya. Egoisme akan 285 menjadi perkara besar dan berbuntut panjang. Aspirasi yang disampaikan harus menjadiwarning sehingga perlu didengarkan oleh pihak perusahaan perkebunan. Seperti penolakan masuknya perusahaan sawit yang berpotensi merusak alam dan lingkungan. Jika aspirasi masyarakat diabaikan, memungkinkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Mendengarkan aspirasi masyarakat adalah tindakan yang efektif menghindari konflik, selagi hak yang menjadi tuntutan masyarakat masih dalam batas kewajaran. Masyarakat sekitar perkebunan kurang mendapatkan perhatian dimana program Corporate Social Responsibility(CSR) tidak dilaksanakan sehingga kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak memberikan dampak bagi perkembangan kemajuan daerah. Oleh sebab itu penolakan atas kehadiran perkebunan kelapa sawit semakin meningkat. 4. Arogansi Pihak Perusahaan Terkadang sikap arogansi ditunjukkan oleh perusahaan yang mengabaikan hakhak karyawannya. Permintaan karyawan untuk mendapatkan upah layak berbuah kepahitan. Karyawan yang telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun tak luput dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tuntutan karyawan cukup beralasan yakni ingin Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam hal ini, perusahaan harus mengambil sikap bijak jika ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebab, ini menyangkut kemajuan perusahaan kedepannya. Permasalahan ini dapat mengundang konflik internal maupun eksternal bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu seringkali pihak perusahaan melakukan melakukan penutupan jalan umum yang sudah termasuk dalam areal perkebunan yang sebelumnya merupakan jalan yang dipergunakan oleh warga sekitar dengan alasan keamanan kebun. Kondisi ini seringkali menimbulkan reaksi, seperti yang terjadi di kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sintang dimana masyarakat berdemo ke perusahaan yang melakukan penutupan jalan. 2. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpualn sebagai berikut: a. Bentuk-bentuk konflik sosial atas pembangunan perkebunan kelapa sawit, antara lain: (1) demonstrasi Kepada Pemerintah Daerah (Bupati / DPRD) untuk menuntut ganti rugi maupun menolak kehadiran perkebunan Kelapa Sawit; (2) pemagaran lahan perkebunan milik perusahaan; (3) Penyitaan / Penyegelan Barang atau Mesin; (4) Pemukulan, penganiayaan dan Pembakaran, dan (5) Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada pihak Perusahaan b. Kerawanan konflik sosial pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dapat dikelompokkan atas beberapa faktor, yaitu: (1) konflik sengketa lahan, (2) lemahnya keadilan dan penegakan hukum, (3) perusahaan mengabaikan kepentingan masyarakat dan (4) arogansi pihak perusahaan dalam menjalan aktivitas usaha. 3. DAFTAR PUSTAKA Alqadrie,Syarief. I. .2004. Pola Pertikaian di Kalimantan dan Faktor-FaktorSosial, Budaya,Ekonomi,dan Politik yang Mempengaruhi Mereka dalam Potret Retak Nusantara (Lambang Trijono,ed).Yogjakarta: CSPS Books. Alpha Amirrachman (Ed.) 2007. Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. Jakarta: ICIP dan European Commission. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Permasalahan yang Menonjol Tahun 2012 di Wilayah Kalimantan Barat yang disampaikan pada acara Rakornas Kominda Se Indonesia Tahun 2012 Hotel Sahid Jaya 18 Juli 2012 286 Elyakim Simon Jalil, 2003. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah di Era Otonomi Daerah: Kasus di Daerah Konflik (Kabupaten Sintang). Makalah dalam Prosiding Lokakarya Nasional di Fakultas Geografi UGM, Jogjakarta, 30 Agustus. Fauziah dkk. 2005. Pemetaan Kerukunan antarumat Beragama di Kalimantan Barat. Laporan Penelitian bersama Balitbang-Puslitbang Kementerian Agama RI. Haryana, Arif Jarot Indarto, Noor Avianto. 2000. Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadila. Jakarta, Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts-II/1990, 519/Kpts/Hk.050/7/1990 dan 23/VIII/90 dan 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan, Otong Rosadi. 2012. Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial: dalam Perenungan Pemikiran Filsafat Hukum, Thafa Media, Yogyakarta, 2012 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Permentan No.26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, Permentan No.14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, Permentan No.7 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Permentan No.36 tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Dirjenbun No.174 tahun 2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional. Rahmaniah, Herlan, Donatianus. 2013. Pemetaan Rawan Konflik Sosial Di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil Penelitian kerjasama Antara FISIP UNTAN dengan Dinas Sosial Provinsi kalimantan Barat. Pontianak (Tidak diterbitkan). Ridwan, Zaenudin & Ibrahim. 2007. Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat. Dalam Alpha Amirrachman (ed.). Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. Jakarta: ICIP dan European Commission. Ridwan Lubis (ed.). 2005. Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara. Jakarta: Balitbang Diklat-Puslitbang Kehidupan Beragama, Kementerian Agama RI. Satjipto Rahardjo, Transformasi Nilai-niloai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional, Seminar BPHN 1995. Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2014, Pontianak. http://disbun.kalbarprov.go.id/ Suteki Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafra Media Yogyakarta, 2013 Susan,Novri.2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Undang-undang No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.41 tahun 2000 tentang Kehutanan, Sumber Internet: Antara news.comhttp://www.antaranews.com/berita/301626/tokoh-di-singkawangsepakat-damai 287 Borneo Tribune, Kisruh Nanga Jetak: Bernard Tersangka Penganiayaan. Editor: Adi M. Chandra http://ditjenbun.pertanian.go.id/setditjenbun/berita-238-pertumbuhan-areal-kelapa-sawitmeningkat.html. Jumat, 21 November 2014 - 16:13:16 WIB Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit Meningkat http://groups.yahoo.com/neo/groups/tionghoa-net/conversations/topics/104859 http://andhikaphantomhive.blogspot.com/2012/01/konflik-sara.html http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2010/06/naga-meliuk-warga-bertumbuk.html http://rri.co.id/index.php/berita/76067/MK-Tolak-Permohonan-Sengketa-PemilukadaKabupaten-Kubu-Raya#.UoGb2lvH2P4 http://www.sayangi.com/daerah1/read/6284/rusman-ali-menang-di-pilkada-kubu-raya http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T0O9SELKDEB0744E2 Kompas.com:http://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/03354875/twitter.com www.kompas.com, Biang Rusuh Lapas Sintang, Napi Eks Singkawang, terbit Jum`at 27 September 2013. Editor: Glori K. Wardianto. www.tribunpontianak.co.id. Kronologis Rusuh di Lapas Sintang. Terbit 25 September 2013. Editor: Susilawati. www.tribunpontianak.co.id. FKPD Sintang Tolak Ketum FPI, terbit Minggu 11 Maret 2012. www.beritasatu.com. Ditempeleng Kalapas, Napi Sintang Kalbar Rusuh. Terbit Rabu 25 September 2013. www.aruemonitor.co. Lapas Sintang Rusuh, 1 Polisi terluka. Terbit Rabu 25 September 2013. Editor:Aceng Mukarram. www.actual.co. Lapas klas 2 B Sintang Kalbar Rusuh, 1 Polisi terluka. Terbit Rabu 25 September 2013. Editor: Aceng Mukarram. www.kalimantan-news.com. Sikapi Penolakan Kehadiran Ketua FPI, Tokoh Agama Minta Masyarakat tetap Jaga Kerukunan. Diterbitkan 14 Maret 2012. Editor: Petrus Heri Sutopo. www.kalimantan-news.com. Bangun Sistem Peringatan Dini Konflik Investasi. Diterbitkan 21 April 2011. Editor: Heri www.kompasiana.co.id. Berbagai aksi penolakan FPI di Kalimantan Barat. Diterbitkan 16 Maret 2012. www.teribunnews.com.Coffee Morning Kodim Sintang Antisipasi Konflik Kebun. Terbit Rabu 25 Januari 2012. Editor: Slamet Bowo Santoso www.equator-news.com. Pabrik PTPN XIII Nanga Jetak Rusuh. Diterbitkan Senin 22 September 2008. Laporan Walhi Kalbar. www.pontianakpos.com . Polisi Usut Pengrusakan Pos Satpam. Diterbitkan Selasa 23 September 2008. www.mongabay.co.id. Lima Masalah Utama Pemicu Konflik HTI di Kalbar. Diterbitkan 29 Juli 2013. Editor: Andi Fachrizal. 288 289 EKOLOGI DALAM PERGULATAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT Siti Aminah Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga [email protected] Abstrak Artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena pergulatan tanah ulayat yang melibatkan negara, masyarakat adat dan investor dengan menggunakan perspektif politik ekologi. Ada dua hipotesis yang dibangun dari paper ini, yaitu: dalam konteks kekuasaan, ada keterkaitan terjadi ketika negara membuat kebijakan intensifikasi pertanian modern yang berciri padat teknologi dan modal. Bagaimana tanah ulayat menjadi area yang acap menjadi ajang konflik antara tiga pihak tersebut. Pertama, kecenderungan praktik dari politik ekologi yang telah menimbulkan resistensi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat. Kedua, dari konflik tiga pihak tersebut mengantarkan pada terbitnya regulasi (Peraturan Daerah) yang menguatkan posisi tawar masyarakat adat untuk mengelola tanah ulayatnya. Dengan perspektif politik ekologi dapat menjelaskan bagaimana faktor politik memengaruhi kebijakan negara dan investor dalam intensifikasi pertanian dan memberi dampak pada terjadinya konflik antara ketiga pihak tersebut. Artikel ini diakhiri dengan melihat implikasi dari analisis untuk membayangkan rasionalitas masyarakat adat untuk melakukan gerakan sosial atau resistensi dalam upaya mempertahankan tanah ulayatnya. Kata kunci: Politik Ekologi, Tanah Ulayat, Resistensi Masyarakat Adat, Gerakan Sosial Abstract The phenomenon of communal land struggle around Merauke areawhat chance do indigenous people stand against multinationals/corporations and state. It is warning state and corporation fearing local anger and many grand investment plans have failed here. This research departed from an attempt to explain interlink between state and corprations to make modern agricultural intensification policies based on solid technology and capital. In reality, there is conflict between corporations and local customary community. There is rationality of local customary community to resistance in order to maintain the rights of legal ownership. In this context, the existence of the state seemed to vanish. This study uses political ecology approach. In this case reveals, it has been two trends practices of political ecology related with the struggle of indigenous peoples' lands to obtain legal certainty. First, there is resistance in defending indigenous communal land. Second, conflict between the state vis a vis the corporation and the corporation vis a vis indigenous people. This conflict became as an instrument for local indigenous people to delivers regulation of communal land (local laws). The indigenous people want to survive as a culture and protect their land. Keywords: Politicalecology, Communal Land, State, Corporate Interest, Indigenous Peoples 290 1. PENDAHULUAN Urgensi penelitian ini adalah terkait dengan pengembangan food estate di Kabupaten Merauke yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo. Implementasi program food estate membutuhkan pengadaan lahan dalam jumlah ribuah hektar. Hal ini menimbulkan serangkaian problema sosial politik ekonomi dan ekologi. Problema muncul karena status tanah di Kabupaten.Merauke, Papua itu dimiliki masyaraat adat yang didalamnya melekat hak ulayat, sehingga adalah tanah itu sebagai tanah ulayat dan pola penguasaan dan pengelolaan tanah berada di tangan masyarakat adat (suku-suku/clan). Yang menarik dari kajian ini adalah ketika pemerintah sebagai pencanang kebijakan, masyarakat adat sebagai aktor sosial yang tanahnya terkena kebijakan, dan korporasi yang digandeng pemerintah untuk menjalankan dan merealisasi perwujudan food estate. Interaksi tiga pihak antara aktor negara, aktor sosial, dan aktor ekonomi ini acap menimbulkan gesekan kepentingan. Dari perpektif politik ekologi, program food estate itu melibatkan interaksi antara aktor negara, masyarakat dan aktor ekonomi berinteraksi dalam kontekstualisasi (kerusakan) lingkungan. Dalam interaksi tersebut ada muatan kapitalisme dan degradasi lingkungan itu akibat eksploitasi alam dan tekanan terhadap lingkungan terlalu kuat dan negara tidak mampu mengontrolnya. Paul Robbins (2004: 12) berpendapat bahwa politik ekologi politik menawarkan eksplorasi berbasis penelitian untuk menjelaskan keterkaitan kondisi dan perubahan sistem lingkungan termasuk lingkungan sosial dan perubahan itu yang mencakup perubahan dalam hubungan kuasa. Fokus penelitian ini: pertama, praktik dari politik ekologi yang terlihat dalam program food estate di Merauke telah menimbulkan resistensi/protes sosial masyarakat adat terhadap aktor ekonomi (korporasi dan investor) yang menyewa tanah ulayatnya. Kedua, resistensi/protes sosial yang dilakukan masyarakat adat (aktor sosial) menyulut konflik ketiga aktor (negara, korporasi, dan masyarakat adat). Konflik tersebut berdampak pada pemalangan tanah adat yang sudah disewakan kepada korporasi dan dapat berujuang pada upaya penerbitiuan Raperda. Kedua permasalahan tersebut dalam perspektif politik ekologi (neomarxian) merupakan pergulatan manusia dalam mengakumulasi nilai lebih. Karena asumsinya, konflik dan kultur modernisasi di bawah ekonomi politik kapitalis global sebagai kekuatan utama dalam membentuk kembali dan menggoyahkan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia, baik masyarakat adat maupun kapitalis mengeksploitasi kekayaan alamnya (hutan) sehingga menggeser fungsi ekologi hutan. Implikasinya, sehingga satwa dan fauna hilang dan rusak. Di Merauke, hutan sebagai tanah ulayat sudah banyak lokasi industri sudah menggeser eksistensi hutan adat dan mengubah kehidupan masyarakat adat menjadi mahkluk ekonomi sesaat. Di balik peristiwa protes sosial dan konflik antara aktor negara, aktor sosial, dan aktor ekonomi sebenarnya yang terjadi adalah penghindaran risiko. 2. TINJAUAN PUSTAKA Mewujdukan program food estatemembutuhkan lahan dalam jumlah besar dan kebutuhan lahan itu tidak mudah. Karena lahan di Merauke adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat (hukum) adat. Sehingga mereka memiliki hak yang disebut hak ulayat. Keterkaitan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 291 1960, pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaa hak ulayat dan hak-ak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehinggga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi.” Singkatnya, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suku (clan), sebuah serikat desa-desa atau satu desa untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat atau tanah bersama berada dalam kelompok yang dipimpin kepala adat. Ada yang mengartikan hak ulayat/hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah itu, terutama menyangkut hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah, dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya termasuk berburu binatang yang hidup di atas tanah itu. Jika program food estate dapat berhasil maka harus ada perubahan fungsi hutan (adat). Perubahan fungsi hutan adat menimbulkan banyak dampak ikutannya (sosial, kultural, ekologi, politik, dan ekonomi). Hal ini menjadi salah satu urgensi dari penelitian ini. Program food estate berhasil jika pemerintah dapat membuat keputusan politik yang bisa menjembatani protes sosial dan konflik antara masyarakat adat dan korporasi. Yang terjadi, masyarakat adat tidak berkonflik via a vis dengan negara, tetapi dengan korporasi sehingga relasi antara masyarakat adat dan korporasi berada dalam rentang protes sosial dan konflik. Baik protes sosial maupun konflik antara masyarakat adat dan korporasi merupakan fungsi dari bekerjanya kapitalisme. Protes sosial yang digelar oleh masyarakat adat (indigenous people) merupakan respon terhadap bekerjanya kekuatan kapitalisme yang dipandang sudah membuat eksistensi hutan adat berubah (luas dan fungsinya). Perubahan eksistensi hutan adat akan merubah eksistensi masyarakat adat. Ini yang menjadi problema rumit yang acap menjadi rintangan dalam implementasi program food estate. Perspektif politik ekologi menjadi salah satu alat analisis yang menjelaskan tentang problema ekologi bukan disebabkan oleh faktor ekologi itu sendiri, tetapi karena faktor politik. Bryant (1992) bahwa masalah ekologi adalah masalah politik. Perubahan ekologi disebabkan oleh kekuatan politik dan kondisi ekologi (lingkungan) yang berubah dipastikan menimbulkan konsekuensi terhadap ekologi dan relasi sosial, politik maupun ekonomi masyarakat(Lowe dan Rüdig, 1986). Ini diperkuat oleh pendapat Bryant dan Bailey (1997)yang menyatakan bahwa politik ekologi memiliki fokus yang mendalami interaksi antara aktor negara, non-negara, dan ekologi fisik. Penerapan pendekatan politik ekologi pada dasarnya merupakan pendekatan yang dapat menguak dan menelusuri degradasi lahan. Ini sudah dimulai sejak Blaikie (1987). Penerapan pendekatan politik ekologi dalam kajian ini relevan. Kajian ini menganalisis dampak dari program food estate (perwujudan program Merauke sebagai lumbung pangan nasional dan internasional) dan program serupa sebelumnya (Integrated Food and Energy Estate- MIFEE) yang mengambil area di Merauke, Papua yang telah menyebabkan masyarakat adat terus bergelut dalam protes sosial dan konflik dengan korporasi/investor. Masyarakat adat mengalami kondisi ketidakpastian secara sosial dan ekonomi. Karena masyarakat adat sudah tidak dapat mengelola tanahnya sendiri dan secara tidak langsung, tidak ada cara lain untuk mengembalikan kedaulatan hidup mereka seperti semula, sehingga mereka melakukan pamalangan atau memimnta bagi hasil kepada kooporasi yang mengelola tanah ulayatnya tersebut. Pengelolaan lingkungan di Merauke tak lepas dari bentuk relasi kuasa seperti yang disinyalir Smith sebagai geografer marxian yang mendalami politik ekologi bahwa lingkungan juga merupakan persoalan kapitalisme (1984). Karena, semua mode 292 kapitalisme akan terus menerus memproduksi dan memperbanyak nilai guna yang memuat entitas secara kualitatif dan nilai itu juga dirancang untuk memiliki manfaat, baik praktis maupun simbolik. Masyarakat adat di Merauke tidak hanya menjadi subsistem dari sistem kapitalisme, tetapi mereka sudah mempraktikan ekonomi kapitalis dalam hidupnya seharihari. Tanah adat sebagai tanah ulayat disewakan (karena tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan) kepada investor/korporasi untuk memperoleh uang. Kemudian uang tersebut digunakan untuk konsumsi memenuhi kebutuhan hidup. Bisa dikatakan, masyarakat adat sudah masuk kedalam perangkap kapitalisme, sehingga kerusakan alam (degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan: flora dan fauna) terjadi bukan karena sistem kapitalis yang mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebih semata-mata, tetapi juga masyarakat. Kerusakan lingkungan hutan adat bukan eksploitasi alam yang dilakukan korporasi sebagai faktor tunggal, tetapi faktor kapitalisme yang sudah memasuki kehidupan masyarat adat dan mengubah pemahamannya tentang nilai ekonomi hutan. Apapun yang bernilai uang akan dijual kepada investor/korporasi. Roh kapitalisme sudah merambah menjadi norma baru atau bisa disebut sebagai nilai baru masyarakat adat. Dalam hal ini terjadi perubahan yang asimetris karena masyarakat adat itu kondisinya masih dalam taraf peradaban meramu dan berburu, tetapi pola dan gaya hidupnya menggantungkan diri pada uang dan subsitensi konsumsi. Uang yang diperoleh hari inidihabiskan untuk hari ini pula, caranya adalah dengan mengkonsumsi barang yang dianggap menjadi kebutuhan hidupnya (apapun dibeli: rokok, sirih pinang, gula, kopi dan mie instant, dan barang lain). Kehidupan konsumtif dan subsistensi ini bukan semata-mata akibat mereka mengenal nilai uang tetapi juga ada faktor lain berupa lompatan perkembangan masyarakat. Masyarakat di Merauke mengalami transisi dari berburu/meramu ke sistem kapitalisme. Dengan terpenuhinya kebutuhan hari ini sudah maka mereka lupa bahwa uang yang mereka miliki sudah habis dan tidak bisa ada lagi uang untuk kehidupan di hari-hari selanjutnya. Ini suatu awal yang dalam pandangan orang luar tentang masyarakat adat bahwa investor/korporasi sudah merubah pola hidup mereka dan menyebabkan munculnya tatanan kehidupan baru yang berbasis pada nilai uang dan hal ini kemudian menjadi ketidakteraturan kehidupan mereka. Jika sudah tidak ada uang , mereka akan melakukan protes sosial atau melakukan pemalangan, dst. Tindakan mereka mendapat legitimasi kuat secara adat karena tanah yang mereka sewakan kepada investor atau korporasi dapat ditarik kembali karena eksistensi tanah yang mereka sewakan adalah tanah ulayat. Problema dalam penyewaan tanah ulayat untuk mewujudkan program lumbung pangan di Merauke akan selalu melibatkan interaksi tiga aktor. Interaksi politik ekologi itu sudah melampaui interaksi politik ekonomi. Artinya, negara, masyarakat adat dan korporasi berinteraksi tidak hanya dalam rentang bidang politik ekonomi, melainkan ekologi. Hal ini dapat dilihat dari praktik masyarakat yang terus menerus berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk itu disadari atau tidak disadari mereka menjalin suatu relasi sosial khusus untuk mendukung praktik kapitalisme di Merauke. Dalam relasi kapitalisme selalu ada relasi yang memperbesar kepemilikan, pertukaran dan persaingan. Akumulasi uang itu bersifat subsistensi karen berapapun yang yang mereka peroleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk hari ini. Dalam konteks ini benar yang disampaikan oleh Smith bahwa “...ada suatu suatu keharusan yang diberlakukan secara sosial" (1984). Dengan relasi seperti ini ini membuat sirkulasi barang dan jasa dalam rantai komoditas yang ini dipandang sebagai kehidupan yang wajar. Jadi masyarakat adat sudah terikat pada norma ekonomi. Kemudian ini berkembang dan menjadi gesekan kepentingan. Gesekan itu berada dalam rentang mulai dari protes sosial, konflik terbuka sampai pada gerakan sosial yang dalam realitasnya berbentuk pembakaran lahan, penutupan area pertanian oleh marga yang punya otoritas untuk itu. Tidak setiap protes sosial dan konflik 293 terbuka yang dilakukan masyarakat terhadap korporasi yang memegang lisensi atau mengelola lahan untuk kegiatan tanaman industri dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, kerena untuk mencapai tahap negosiasi ada masalah internal dalam marga yang meguasai lahan itu dan umumnya yang terjadi adalah setiap lahan dikuasai oleh marga yang dominan dan kuat. Marga yang kuat ini melakukan negosiasi dengan korporasi yang menyewa lahannya, sementara marga-marga lainnya tidak dilibatkan dalam proses negosiasi dan bahkan tidak memperoleh pembagian uang sebagai bentuk kompensasi materi yang diberikan korporasi kepada marga sebagai salah alternatif cara dalam menyewa tanah ulayat mereka. 3. METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian adalah kualitatif karena mengeksplorasi fenomena tentang protes-protes politik dari masyarakat adat yang tanah ulayatnya mengalami transformasi fungsi. Hutan adat beralih fungsi menjadi area untuk tanaman produktif padi atau untuk pengembangan sistem pertanian modern. Penelitin ini berlokasi di Kab. Merauke karena kabupetan ini menjadi wilayah pengembangan food estate yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Unit analisis penelitian ini ialah pemerintah (aktor politik), masyarakat adat (aktor sosial), dan korporasi (aktor ekonomi). Ketiga aktor ini berelasi dalam satu program yaitu food estate di Kab. Merauke. Proses pencarian informan yang berasal dari institusi digunakan melalui teknik penjajagan dan pelacakan informan sesuai dengan keahliannya dan menjadi person yang memiliki peran atas perencanaan dan pengembangan area food estate, pelaku usaha, masyarakat, tokokh adat, tokoh agama, pemerintah da aktor sosial lainnya yang terlibat dalam program pengembangan food estate. Informasi dari informaninforman itu kemudian dipelajari dan dipertimbangkan secara metodologis untuk selanjutnya diwawancara dalam konteks menjaring data perencanaan tata ruang Surabaya. Sedangkan untuk wawancara dengan informan yang bersifat personal digunakan teknik purposive. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: pengamatan, wawancara mendalam, dokumentasi (kajian literatur/jurnal tata ruang elektronik maupun non elektronik), dan diskusi dengan tim ahli. Teknik pengamatan untuk merekam data primer dengan memperhatikan kondisi factual di lapangan. Teknik wawancara mendalam untuk menggali data primer dilakukan dengan beberapa informan (nara sumber). Untuk memperoleh informan/narasumbermenggunakan teknik pemilihan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian. Sedangkan dota BPS sebagai data untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi dan demografis masyarakat Kab. Merauke. Penelitian ini jugamelakukan kajian literatur maksudnya adalah mempelajari hasil-hasil riset sejenis untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan antara perencanaan dan implementasi tata ruang kota dan peruntukannya. Analisis data menggunakan teknik analitik eksplanatif, di mana semua data lapangan diseleksi, dipilah kemudian dianalisis dan diinterpretasi berdasar aspek-aspek yang diteliti dengan memperhatikan konsep/teori yang digunakan. 4. TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN Luas Kabupaten Merauke adalah 46.791,63 km2 (Merauke dalam angka, 2013), yang terdiri dari 20 distrik dengan distrik terjauh adalah distrik Muting yaitu 247 kmdari ibukota kabupaten. Distrik Waan merupakan distrik terluas yaitu mencapai 5.416,84 km2 atau sekitar 11,58% dari total luas areal diikuti oleh Distrik Ulilin seluas 5.092,57 km2 atau 10,88%. Kondisi Demografi Kabupaten Merauke merupakan Indonesia Mini karena penduduk Merauke sudah heterogen dari berbagi etnis yang ada di Nusantara ini mulai dari suku asli Merauke (Marind, Jei, Kanum dan Kimaam) juga suku suku lain seperti Maluku, Timor, Bugis Makasar, Menado, Banjar, Dayak, Jawa, Batak dan Aceh juga ada di 294 Merauke ini.Hasil pendataan Biro Pusat Statistik dan juga data Pemerintah Kabupaten Merauke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukan bahwa jumlah Penduduk yang Non Papua lebih besar mencapai 63 % dari jumlah penduduk kurang lebih 185.718 jiwa dan sebagaian besar adalah suku Jawa. Hal ini disebabkan sejak masa bergabungnya Irian Barat ke Pangkuan NKRI tahun 1963 sudah ada upaya Pemerintah mendatangkan Transmigrasi yang ditempatkan pada Pinggiran Kota Merauke (Sidomulyo, Kumbe dan Kurik). Dan pada masa orde Baru era Tahun 80-an kembali program Transmigrasi digalakkan dalam rangka pemerataan penduduk sekaligus mengolah sumberdaya alam dengan potensi pertanian yang besar. Wilayah pemerintahan pada Kabupaten Merauke terdiri dari 20 Distrik (Kecamatan), 8 (delapan) Kelurahan dan 160 (Seratus enam puluh) Kampung/desa. Tabel.1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik DiKabupaten Merauke Jumlah Jumlah Kampung kelurahan 1 Kimaam 4.630,30 11 2 Waan 2.868,06 8 3 Tabonji 5.416,84 9 4 Ilyawab 1.999,08 4 5 Okaba 1.560,50 8 6 Tubang 2.781,18 6 7 Ngguti 3.554,62 5 8 Kaptel 2.384,05 4 9 Kurik 977,05 9 10 Malind 1.465,60 7 11 Animha 490,60 5 12 Merauke 1.445,63 2 8 13 Semangga 905,86 10 14 Tanah Miring 326,95 14 15 Jagebob 1.516,67 14 16 Sota 1.364,96 5 17 Naukenjerai 2.843,21 5 18 Muting 3.501,67 12 19 Elikobel 1.666,23 12 20 Ulilin 5.092,57 11 Sumber: RTRW Kabupaten Merauke Tahun 2013 Jumlah dan Distribusi Penduduk pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Merauke berjumlah 70,002 jiwa yang menempati wilayah seluas 1.445,63 km2, dengan komposisi penduduk laki-laki 35,974 jiwa (51,39 %) dan perempuan 34,028 jiwa (48,61%). Sex ratio penduduk Kabupaten Merauke sebesar 105,72. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat sekitar 100 orang laki-laki. Kepadatan tiap Distrik yang ada di Kabupaten Merauke tidak merata. Berdasarkan konsentrasi penduduk per distrik didapatkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kabupaten Merauke berada di wilayah Distrik Merauke yaitu 38,5 jiwa/km2, sedangkan konsentrasi yang terendah adalah di Distrik Kaptel dan Distrik Ngguti yaitu masing-masingnya 0,6 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Merauke adalah 3,8 jiwa per km2. Terkonsentrasinya jumlah penduduk di Distrik Merauke disebabkan oleh tersedianya fasilitas pelayanan umum di distrik tersebut, dimana distrik-distrik lain di wilayah kabupaten ini banyak yang belum terbangun. Bahkan sebagian besar distrik-distrik baru No Distrik Luas (Km2) 295 belum terbangun sama sekali baik dari segi fasilitas pelayanan maupun dari segi infrastruktur. Faktor lainnya adalah tingginya bangkitan kegiatan di distrik tersebut dibandingkan distrik lainnya. Distrik-distrik lain yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Distrik Semangga, Distrik Malind dan Distrik Kurik. Ketiga distrik tersebut sebelumnya adalah merupakan kawasan transmigrasi. akan tetapi telah berkembang menjadi pusat-pusat permukiman baru bagi masyarakat pendatang lainnya. Faktor kedekatan ketiga Distrik ini dengan Kota Merauke serta didukung dengan akses jaringan jalan yang baik ke ibukota kabupaten merupakan salah satu fakta menarik bagi penduduk yang ingin mencari pekerjaan di Kota Merauke. Khusus untuk Distrik Semangga dan Kurik, di Distrik ini juga terdapat desa-desa yang dihuni oleh penduduk perintis, yaitu penduduk pendatang non transmigran yang telah berpuluh tahun tinggal di Merauke. Sektor utama yang berkembang di Kabupaten Merauke selama ini adalah sektor pertanian dan subsektor yang sangat kuat menunjang perekonomian Kabupaten Merauke adalah pertanian lahan basah dan pertanian lahan basah, perikanan, dan peternakan dikarenakan sumber daya alam yang banyak tersedia di Kabupaten Merauke adalah sumber daya pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri yang tepat untuk di Kabupaten Merauke adalah industri yang inputnya dari pertanian, yaitu industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan tersebut tanpa menganggu eksistensi hutan adat. - Sewa Tanah, Hak Ulayat dan Degradasi Ekologi Penyewaan tanah (adat) ke korporasi melalui mekanisme pelepasan adat dan ini menghadirkan aktor-aktor yang menjadi representasi negara seperti TNI Angkatan darat, Kepolisian, Pemerintah Distrik, dan tokoh-tokoh adat dan ketua marga yang menandatangani surat pelepasan sebagai proses mengadministrasikan tanah yang disewakan kepada korporasi dan upacara adat itu juga sebagai bukti bahwa pelepasan itu merupakan bentuk negosiasi dari masyarakat adat terhadap korporasi yang menjalankan program pemerintah. Pada pelepasan tana adat tersebut ada acara Toki Babi atau makan Pinang sebagai serangkaian acara dan dalam upacara tersebut mereka melakukan sumpah bersama, sumpah dengan darah ataupun sumpah atas nama tanah air untuk tidak akan mengganggu kepemilikan tanah yang telah dilepas ini. Hukuman yang tidak ditaati akan menuai karma, begitu keyakinan kuat yang dipegang dalam kehidupan masyarakat adat. Pelepasan tanah adat/tanah ulayat yang akan disewakan harus melalui upacara adat dan pelepasan tanah adat sesungguhnya sebagai cara untuk melegitimasi adanya perubahan atas fungsi tanah adat menjadi tanah untuk kegiatan industri dan investasi (kepentingan kapitalis) dan menghindari konflik. Meski sudah ada pelepasan untuk proses sewa menyewa, masyarakat adat masih memiliki celah untuk mengembalikan tanah ulatnya yang sudah disewakan ke investor. Ini juga berarti pelepasan hak ulayat diingkari oleh masyaraat adat. Cara yang lazim dilakukan adalah dengan pemalangan. Dengan masuknya investasi skala besar untuk perkebunan ataupun hutan tanaman industri di wilayah Papua bagian selatan dinilai membawa dampak kerusakan ekologi dan memunculkan persoalan sosial. Dua dampak besar adalah kerusakan sosial dan kerusakan ekologi. Ini persoalan besar yang dihadapi oleh warga lokal Merauke. Pembukaan hutan telah merusak sebagian besat sumber kehidupan mereka. Warga kampung di distrik B (nama disamarkan, di kampung ini sebagian tanah ulayat sudah menjadi Hutan Tanaman Industri, di kampung ini pula sudah terjadi kerusakan ekologi yang oarah, banjir). Kamung B ini ada di Distrik Z yang merupakan area industri pertanian modern yang kini masyarakatnya sudah semakin sulit mendapatkan hewan buruan karena pembukaan hutan 296 dan HTI. Menurut informan yang kami wawancara sebagai pendeta dari Klasis Gereja Protestan Indonesia Merauke, berpendapat: ”... Masuknya investasi besar di Merauke memunculkan konflik agraria, baik antara warga pemilik tanah ulayat dan perusahaan maupun antarwarga sendiri (antarmarga). Konflik agraria muncul karena lemahnya regulasi karena belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tanah hak ulayat sehingga posisi masyarakat adat lemah. Lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam mengelola hutannya menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan karena mata pencaharian masyarakat terganggu dan dampak lingkungan seperti kerusakan ekosistem juga tak dapat dihindarkan...” (wawancara 30 Oktober 2015). Pemerintah memberikan penjelasan bahwa dengan pertanian modern, masyarakat asli lebih diuntungkan karena bisa panen tiga kali setahun dan dapat uang dari sewa lahan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ada dalam bayangan masyarakat lokal adalah uang dan uang. Mereka tertarik untuk melepaskan dan menyewakan tanahnya kepada perusahaan karena uang yang akan diterima dalam jumlah besar. Tiga kali akan menerima uang hasil dari bagi hasil. Uang yang diterima akan dihabiskan dalam waktu singkat sehingga keberlanjutan atau kelangsungan hidup masyarakat lokal menjadi taruhannya. Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat lokal yang hidupnya masih bergantung pada kondisi alam (berburu dan meramu). Harapan masyarakat di Merauke adalah pembangunan lumbung pangan dan investasi lainnya idealnya dapat membawa dampak yang baik untuk keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Aspek pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di wilayah itu tetap penting karena mereka adalah pewaris dan pemilik sumber daya tersebut.Pertikaian yang ada di kampung A (sebagai nama samaran) menurut informan adalah konflik warga dengan PT X terkait masalah penggunaan lahan ulayat yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Oleh karena warga belum memanfaatkan lahan untuk pertanian maka hingga saat ini tidak pernah ada problem terkait bencana kelangkaan pangan baik akibat gagal panen maupun serangan hama. Belum pernah ada ancaman terhadap aset masyarakat secara musiman, baik karena gangguan binatang, kebakaran hutan maupun hujan apalagi sampai menyebabkan kenaikan harga pangan. Yang terjadi saat ini adalah kenaikan beberapa komoditas akibat pengaruh ekomomi nasional yang berimbas sampai ke kampng-kampung di Merauke. Hutan yang merupakan sumber pangan dan obat serta sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat adat setempat, sebagian sudah hilang dan berganti mejadi perkebunan atau HTI. Ini menyebabkan masyarakat untuk mencari rusa dan babi hutan saja harus berhari-hari tinggal di hutan. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pertemuanpertemuan di kampung sangat kurang. Apalagi, pertemuan terkait tanah adat sangat tertutup dan perempuan tidak pernah dilibatkan. Larangan menjual tanah untuk masa depan anakanak dan cucu seakan hanya angin lalu. Sekarang, mereka yang menanggung bebanberat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berjalan kaki berkilo-kilo hanya untuk mencari sumber air bersih dan kayu bakar. Padahal dulu, mereka hanya melangkah dibelakang rumah dan menggunakan air bersih dari rawa sagu. Hak ulayat terancam dengan adanya investasi besar yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Merauke. Kejadian ini berpotensi menghilangkan hutan alam masyarakat. Sementara itu bila kita melihat lebih jauh ke belakang, secara turun-temurun masyarakat lokal penghidupannya bergantung dari kekayaan alam, termasuk kekayaan hutan; pengelolaan hutan dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara yang sederhana berdasarkan pengetahuan setempat; kebutuhan air bersih. Pemanfaatan hasil hutan masih sebatas untuk kebutuhan rumah tangga saja dan tidak membutuhkan teknologi yang 297 merusak hutan secara cepat. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, maka dalam pengelolaan hutan kiranya masyarakat adat juga dilibatkan. Menurut informan yang berposisi sebagai kepala dusun, dengan rencana pemerintah membuka pertanian modern maka setiap tiga bulan masyarakat sudah bisa panen padi. Sehingga masyarakat mendapat sumber pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Jokowi sudah menyampaikan informasi ke perusahaan, nanti perusahaan akan meneruskan informasi tersebut agar masyarakat bisa tanam padi. Warga berharap sistem yang diggunakan nantinya adalah sistem sewa-tanah masyarakat. Kalau menggunakan sistem pelepasan tanah, dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak mendapat warisan tanah. Informan tersebut berpendapat: “...Warga berharap sistem yang digunakan nantinya adalah sistem sewa-tanah yang tidak mengancam kelansungan atau eksistensi hutan adat. Dikhawatirkan menggunakan sistem pelepasan tanah, generasi yang akan datang tidak mendapat warisan adat serta tanah adat, yang berarti ini akan menghilangkan adat Papua/Merauke. Jangka waktu sewa tanah tergantung sepenuhnya kepada pemilik dusun. Biasanya 20 atau 30 tahun. Masyarakat akan tunduk kepada Kepala Dusun, apapun keputusan Bapak Kepala Dusun itu merupakan hak setiap Kepala Dusun. Biasanya keputusan dibuat berdasarkan rundingan diantara 8 marga di Buepe. Kalau satu dusun menyetujui sistem sewa tanah kepada perusahaan maka bisa disewa. Jika satu diantara delapan (8) marga tidak menyetujui, itu tergantung dusunnya. Dengan demikian, persetujuan sewa tanah oleh perusahaan sangat tergantung pada keputusan Bapak Kepala Dusun...” (wawancara 29 Oktober 2015) Protes sosial kepada korporasi kembali terjadi dan pemicunya adalah bagi hasil yang belum mereka terima. Problema ini menjadi semakin rumit jika ujung dari tuntutan yang tidak terpenuhi ini pemalangan. Korporasi sudah memberikan fasilitas yang mereka butuhkan berupa listrik, air bersih, dan perumahan layak huni. Tanpa terelakkan, dengan pelepasan tanah adat melalui prosesi adat dan bagi hasil serta pembangunan fasilitas bagi masyarakat adat tampaknya sebagai cara yang sudah menyelinap dalam pikiran ketiga aktor. Artinya, yang awalnya kita tidak mau berisiko dengan program food estate, justru tanpa sadar kita tampaknya menyelinap menuju masyarakat risiko sebagaimana dibayangkan oleh Ulrich Beck (1992), di mana hidup dan politik diorganisasi sekitar penghindaran risiko. Namun, dalam hal pengelolaan tanah adat dan degradasi lingkungan setidaknya ada dasar penyebab dari risiko lingkungan yang ini merupakan implikasi dari solusi dan kesepakatan untuk risiko.Keprihatian dalam mencapai tujuan mewujudkan lumbung pangan tak lain sebagai ungkapan keprihatinan atas kondisi ekologi dan politik ekonomi politik yang kini tengah terjadi di Merauke.Ketidakpuasan/ketidaknyamanan masyarakat indigenous atas hasil kontrak sewa menyewa tanah adat/ulayat dengan perusahaan terus menjadi kendala dan masyarakat adat masih terus menunggu janji-janji yang pernah disampaikan oleh korporasi sebelum melakukan pelepasan tanah adat dan sebelum dimulainya operasi perusahaan untuk mengelola HTI. - Berebut Alih Kelola Tanah Ulayat: Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mendukung eksplorasi sumberdaya alam yang berada di Merauke dan hal ini telah menyebabkan terpinggirkannya masyarakat adat dari pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan. Masyarakat adat memiliki keterbatasan dalam aspek sumberdaya karena pengelolaan sumberdaya alam dan lahan dilakukan dengan teknik dan teknologi sederhana. Sementara perusahaan (korporasi menggunakan teknik atau teknologi pertanian mekanis dan padat teknologi). Akibat dari pola pengelolaan lahan yang berbeda ini mengakibatkan masyarakat adat (indigenous people) tidak mampu 298 bersaing dengan kekuatan korporasi. Ketidakmampuan bersaing dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya itu yang menyebabkan masyarakat adat berusaha keras untuk membatasi ruang gerak korporasi untuk mengeksplorasi sumberdaya alam dan pemanfaatan lahan. Cara yang biasa digunakan oleh masyarakat adat adalah secara adat. Artinya masyarakat menolak kehadiran perusahaan yang mengeksplorasi dan mengelola sumberdaya alam dan lahan menggunakan teknologi canggih pertanian dan modal besar. Karena ini akan berdampak besar terhadap eksistensi dan kehidupan mereka ke depannya. Masyarakat adat meminta pemerintah pusat dan Merauke untuk mengurangi akses atau bahkan menutup akses untuk mengelola tanah ulayat. Tetapi aktor-aktor negara tersebut tidak kuasa karena negara membutuhkan korporasi untuk mewujudkan lumbung pangan di Merauke. Ketika ada konflik antara korporasi dan masyarakat inigenous yang dipersoalkan adalah terkait eksistensi tanah adat. Pemahaman atas eksistensi tanah adat antara korporasi, pemerintah dan masyarakat itu berbeda satu sama lain. Masing-masing aktor tersebut mempersepsi kepentingan dan tanah berdasarkan pengetahuan dan otoritasnya. Yang paling sulit adalah memahami cara berpikir masyarakat indigenous. Rencana pemerintah untuk membangun pertanian modern di Merauke juga harus diikuti dengan rangkaian regulasi yang menjamin eksistensi adat dan perusahaan yang akan beroperasi di wilayah adat Merauke. Karena itu, diharapkan masyarakat juga harus bisa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan sewa menyewa tanah adat ini dan warga indigenous juga bisa menjadi pekerja dalam perusahaan. Perusahaan masuk sudah ada batasnya, tidak semua lahan bisa disewakan kepada perusahaan yang sudah menggunakan sistem bagi hasil dengan perbandingan 30:70, dimana masyarakat adat memperoleh bagian 30 persen hasil usaha korporasi dan 70 persen menjadi hak korporasi. Pemerintah sebagai pemberi lisensi belum mampu secara proporsional menjembatani kesenjangan kepentingan antara dua belah pihak ini (koporasi dan masyarakat adat). Setidaknya pemerintah sebagai penggagas program food estate belum mampu merumuskan resolusi atas konflik/sengketa yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan dua belah pihak. Hal ini mencakup regulasi di tingkat pusat maupun di daerah (Merauke) di bidang tata kelola tanah adat. Bagaimana posisi petani lokal, masyarat adat, masyarakat pendatang (non indigenous people), pemerintah lokal (kabupaten, distrik, kampung), bagaimana posisi perusahaan (konglomerasi agribisnis nasional dan multinasional/asing). Regulasi tentang tata kelola tanah adat untuk food estate juga perlu membatasi ruang perusahaan dari liberalisasi tata kelola tanah. Ini menjadi salah satu titik tekan yang perlu memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang berdampak pada berhentinya kegiatan korporasi/investor dalam mengeksplorasi sumberdaya alam Merauke karena penolakan dan perlawanan masyarakat adat kepada perusahaan. Dalam konteks ini, perubahan sifat hubungan antara pemerintah dengan korporasi dan masyarakat adat sudah berubah. Pemerintah perlu memiliki kemampuan dalam mengatur aktor korporasi dan masyarakat adat. Karena kedua aktor ini memiliki relasi untuk produksi dan distribusi atas sumberdaya hutan adat. Sumberdaya ini kecenderungannya kini lebih banyak disewakan kepada korporasi karena masyarakat adat membutuhkan hutan untuk memproduksi uang. Begitu pula dengan korporasi yang menyewa hutan dari masyarakat adat untuk memproduksi barang dan jasa. Pertarungan dua pihak yang memiliki kepentingan produksi dan distribusi ini mengakibatkan korporasi dan masyarakat adat berada dalam suatu garis linear protes dan konflik sosial.Implikasi dari protes sosial ini, DPRD Kab. Merauke, sudah mengambil langkah strategis dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum Adat dan Hak Ulayat. 5. KESIMPULAN 299 Protes sosial dan konflik atau terjadinya gerakan ekologi sesungguhnya memberi signal kepada pemerintah (negara) untuk mengambil keputusan (politik)dalam kerangka menyelamatkan kehancuran ekologi atau degradasi lingkungan, terutama hutan-hutan adat tempat bergantungnya hidup masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat adat terus tergerus dengan keputusan-keputusan poltik pwmerintah yang hendak mewujudkan lumbung pangan di Merauke. Protes sosial dan konflik yang berbalut tanah ulayat di Merauke merupakan dampak yang sudah dibayangkan oleh Beck (1992) dan ahli-ahli lain dari bidang politik ekologi maupun geografer marxian seperti Neil Smith, Robbins dan lainnya. Konsesi yang diberikan oleh negara kepada korporasi telah menyebabkan korporasi berhadapan dengan masyarakat adat. Ini yang menjadi pemicu adanya ‘pemalangan”. Masyarakat adat memiliki syarat untuk menyewakan lahannya kepada korporasi. Tatanan adat acap tidak kuasa menghadapi kekuatan korporasi dan begitu sebaliknya. Tatanan korporasi tidak kuasa menghadapi tekanan dari masyarakat adat (indegenous). Meski sudah ada perlawanan dari masyarakat adat, tetapi korporasi juga melakukan perlawanan karena korporasi memiliki ijin sah untuk membuka usaha di tanah yang dikuasai masyarakat adat. Ini yang kemudian berkembang menjadi persoalan yang terus berkepanjangan dan menganggu beroperasinya korporasi. Ada beberapa rekomendasi yang bisa diwujdukan dalam kebijakan, antara lain: pemerintah pusat dan lokal seyogianya membangun sinergi dalam hal diplomasi lingkungan karena dengan diplomasi ini memunkinkan adanya saling kesepahaman dalam menggunakan sumberdaya termasuk penggunaan sumber daya alam dan kekayaan lain yang bersumber dari alam. Dengan cara ini diharapkan bisa memecahkan masalah yang muncul dari program food estate. Pemerintah pusat dan daerah setidaknya memperkenalkan lembaga pemerintah terpadu yang memungkinkan untuk merampingkan kegiatan dan menghapus kontradiksi internal. Baik perusahaan maupun pemerintah perlu memperhatikan kapital yang ada dalam komunitas masyarakat adat itu termasuk kapital sosial dan tidak menempatkan masyarakat indegenous sebagai pelaku pasif. Ketika peristiwa pemalangan perusahaan oleh marga terjadi (Sani) maka pemerintah setempat harus segera mengatasinya dengan cara bersinergi dengan asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan lokal yang ada dalam komunitas itu (marga/adat). Karena tidak bisa masyarakat adat/indegenous people itu bertindak secara sepihak melakukan pemalangan atau pemaksaan penutupan area usaha perusahaan, dll. Sebelum kegiatan pemalangan itu menjadi keputusan akhir yang diambil oleh kekuatan marga/kekuatan kolektif, maka semua proses sengeketa atau konflik yang mendahului harus bisa diatasi dengan mensinergikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 6. DAFTAR PUSTAKA Beck, Ulrich. 1992.Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Pub. Blaikie, P. and Brookfield, H. 1987. Land Degradation and Society. London: Methuen. Bryant, Raymond L. and Sinead Bailey. 1997. Third World Political Ecology, NY:Routledge. Greenberg, James B. and Thomas K. Park. 1994. Political Ecology.Journal of Political Ecology 1:1-12. Paulson, Susan, Lisa L. Gezon, and Michael Watts. 2003. “Locating the Political in Political Ecology: An Introduction.” Human Organization 62(3): 205-217 Peet. Richard and Michael Watts Michael Watts (eds.). 1996.Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements. London: Routledge. Robbins, Paul. 2004. Political Ecology: A Critical Introduction. UK: Blackwell Pub. Smith, Neil. (1984). Uneven Development.Oxford: Blackwell. 300 Smith, Neil. 2006. Nature as Accumulation Strategy. Socialist Register, 16-36. Diunduh pada: http://neil-smith.net/category/vectors/production-of-nature. Walker, Peter A. 2006. Political Ecology: Where is the Policy?.Progress in Human Geography 30(3): 382-395. 301 PETANI KECIL DITENGAH AGRIBISNIS KAPITALIS Amruddin Dosen Fak.Pertanian Unismuh Makassar Email : [email protected] Abstrak Pertanian adalah sektor andalan pembangunan Indonesia. Ditengah modernisasi pertanian perubahan struktur pertanian menjadi lebih didominasi petani kecil. Petani kecil merupakan golongan terbesar dalam kelompok petani di Indonesia. Sektor pertanian menawarkan paradigma agribisnis. Gempuran modernisasi berbasis modal di era globalisasi masuk desa membawa dampak ikutan kapitalisme masyarakat. Makalah ini mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi petani kecil disaat desa ditengarai sedang berlangsung agribisnis kapitalis. Studi pendahuluanfokus kepada berlangsungya konversi lahan, pemanfaatan lahan pekarangan serta peluang kerja petani di luar sektor pertanian. Modernisasi pertanian menunjang keberhasilan sektor pertanian berhadapan dengan kencenderungan konversi lahan di Desa Kanjilo. Alihfungsi lahan menyebabkan petani mencoba alternatif bekerja diluar sektor pertanian. Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi strategi petani kecil menambah pendapatan keluarga secara berkesinambungan. Kata Kunci: Petani Kecil, Agribisnis Kapitalis, Modernisasi Pertanian Abstract Agriculture is the mainstay of the construction sector in Indonesia. The modernization of agriculture change the structure of agriculture is becoming more dominated by small farmers. Smallholder farmers are the largest group in the group of farmers in Indonesia. The agricultural sector offers a paradigm of agribusiness. The onslaught of modernization based capital in the era of globalization into the village carrying the outcomes rather than capitalist society. This paper describes the socio-economic life of small farmers while the village is considered ongoing capitalist agribusiness. Preliminary study focused on ongoing land conversion, land use farmer's yard and job opportunities outside agriculture. Modernization of agriculture to the success of the agricultural sector to deal with trends in land conversion in the village Kanjilo. Land use causes farmers to try alternative work outside the agricultural sector. Utilization of yard area into a strategy of small farmers supplement the family income on an ongoing basis. Keywords: Small Farmers, Agribusiness Capitalists, Modernisation Of Agriculture 302 1. PENDAHULUAN Petani sebagai suatu komunitas penting di pedesaan. Pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang bermukim serta menjadi penciri sebagai negara agraris. Pertanian adalah sector adalan pembangunan Indonesia. Sektor pertanian juga merupakan penghela pembangunan atau agriculture led development (Wardoyo, 1993). Pembangunan berdimensi agribisnis bahkan telah dituangkan didalam UU No.18 tahun 2012 untuk menjamin ketahanan pangan secara nasional. Eksistensi petani sebagai instrumen penting keberhasilan sekaligus menopang utama ketahanan pangan menjadi sangat jelas dimata birokrasi NKRI. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pertanian telah berlangsung sangat lama, yang merupakan akumulasi dari berbagai karakteristik yang melekat pada masyarakat pertanian yang subsisten. Dengan usaha yang kecil, terpencil, tradisional, aksesibilitas yang rendah pada modal, teknologi, dan pasar merupakan penyebab kemiskinan yang berkelanjutan. Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Namun di Indonesia, kemiskinan merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi di perdesaan pada umumnya dan disektor pertanian pada khsususnya. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau di sektor pertanian. Dari jumlah penduduk miskin di Indonesia 56,84 % berada di Pulau Jawa dan 43,11% di luar Jawa, sekitar 80% penduduk miskin tersebut berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 20% di KTI. Dominasi terbanyak penduduk miskin ada di perdesaan yaitu 64,3% dan selebihnya 35,7% di perkotaan (Andi Nuhung, 2006). Pada sisi yang lain, masuknya modernisasi pertanian menyebabkan dinamika sosial ekonomi pada masyarakat desa [(Geertz (1983), (Hayami dan Kikuchi (1987), Amaluddin (1987), Abustam (1989)]. Salah satu yang nampak dalam perubahan tersebut adalah terdapatnya polarisasi sosial di pedesaan di Jawa. Selain itu, temuan lain adalah beralihnya petani diluar sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Bekerja diluar sektor pertanian ini terkadang dengan mobilisasi petani ke kota. Masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokok. Beras tidak datang begitu saja dari langit tapi melalui proses panjang. Petani yang bermukin di desa sebagai produsen beras diharapkan terus mensuplai bahan pokok tersebut. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi pertanian, petani diperhadapkan oleh berbagai persoalan. Persoalan klasik adalah ketergantungan pada alam, kondisi musim serta gangguan hama tanaman. Termasuk bagaimana mereka dituntut terus eksis, walaupun pada sisi yang lain luas pemilikan dan penguasaan lahan petani juga tergerus. Kapitalisasi pertanian merasuk sampai ke pelosok desa. Di desa cenderung terjadi kemiskinan struktural daripada kemiskinan alamiah. Hasil sensus pertanian 2013 menjelaskan jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Petani gurem adalah petani yang luas lahannya kurang dari 0,5 hektar (Kompas, 03/12/13). Variabel penting dalam penelitian dengan lokus pedesaan adalah pemilikan dan penguasaan lahan petani. Pemilikan lahan dan penguasaan lahan petani berbeda defenisi. Penguasaan lahan tidak berarti memiliki lahan, penguasaan bisa sebatas sewa, sakap, atau petani hanya sebagai penggarap. Tujuan penelitian adalah rekonstruksikehidupan sosial ekonomi petani kecil di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Penelitian menelusuri petani kecil 303 pemanfaatan lahan pekarangan, peluang kerja diluar sektor pertanian serta konversi lahan pertanian. 2. TINJAUAN PUSTAKA Masuknya teknologi di Pedesaan berdasarkan penelitian Hayami dan Kikuchi (1987) dalam Triyono dan Nasikun (1992) yang menyimpulkan bahwa teknologi baru itu netral skala atau tepat guna bagi petani luas dan guren (petani kecil). Perubahan di pedesaan lebih ditandai oleh proses meningkatnya stratifikasi, yaitu proses dimana masyarakat desa menjadi semakin berlapis-lapis atau makin banyak lapisan-lapisannya daripada gejala polarisasi. Sebelumnya Geertz (1983) mengemukakan bahwa dibawah tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat dan sumber daya yang terbatas maka masyarakat desa Jawa tidak terbelah menjadi dua, yaitu golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak yang diperas melainkan tetap mempertahankan tingkat homogenitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagi rezeki yang ada. Geertz menamakan proses ini sebagai shared poverty. Kondisi ketidaksamaan ekonomis menimbulkan dua kecenderungan yakni stratifikasi dan polarisasi kelas. Kecenderungan pertama menunjuk kepada diferensiasi sosial dalam spektrum kontinum dari buruh tani ke tuan tanah sedangkan hubungan sosial berdasar tradisi komunitas desa tetap terpelihara. Kecenderungan kedua menunjuk kepada pembagian masyarakat secara dikotomi menjadi pengusaha, petani luas dan kaum buruh atau tunakisma sedangkan hubungan sosial berdasar tradisi komunitas desa digantikan oleh hubungan komersial. Proses stratifikasi sosial akan berubah ke arah polarisasi bila ada kondisi-kondisi tertentu di pedesaan yang menyebabkannya berubah arah. Kondisi-kondisi tersebut adalah; (1) distribusi pendapatan atau kekayaan semakin timpang selama proses stratifikasi berlangsung, (2) para elit menjadi lebih memiliki kekuasaan dan cenderung mementingkan persekutuan dengan kekuasaan sosial politik dari luar desa dibanding kesetiaan terhadap sesama warga miskin desa, dan (3) bersamaan dengan itu proses komersialisasi semakin meningkatkan hasrat mereka terhadap barang-barang dan jasa-jasa modern dibanding hasrat mereka untuk beritikad baik terhadap sesama warga (Amaluddin, 1987). Syahyuti (2013) menjelaskan bahwa peasant adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kecil, penyewa, penyakap dan buruh tani. Melekat pada peasant adalah sikap kerjasama satu sama lain, usaha tani kecil dan menggunakan tenaga kerja sendiri. Mereka adalah petani subsisten yang mengutamakan untuk memenuhi konsumsi sendiri. Penguasaan tanah keluarga-keluarga petani di Sulawesi ternyata tidak jauh berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah sejak lama memiliki skema ketimpangan penguasaan tanah petani. Propinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang ketimpangan struktur penguasaan tanahnya paling menyolok dengan luas penguasaan tanah dibawah setengah hektar dimiliki 31,44 % keluarga petani dan 6,25 % lainnya menguasai lebih dari tiga hektar. Keadaan ketimpangan distribusi tanah yang lebih buruk ditemukan di Kabupaten Takalar, Gowa, Pangkep, Barru dan Tanah Toraja (Suhendar dan Winarni, 1997). Aspek penting dalam kegiatan agribisnis dalam persfektif sosiologi adalah organisasi. Konsep cara produksi dapat digunakan dalam hal ini. Untuk itu dapat dirujuk tiga tipe cara produksi yang tampaknya relevan dikenakan pada dunia pertanian Indonesia (1).Produksi Subsisten (subsistence production), usaha pertanian oleh dan untuk rumah tangga petani, (2).Produk Komersialis (petty commodity production), usaha pertanian/luar 304 pertanian skala kecil oleh rumah tangga untuk pasar. (3).Produksi Kapitalis (capitalist production), usaha pertanian/luar pertanian skala menengah/pasar oleh perusahaan untuk pasar. Dengan memadukan tiga tipe agraris menurut kualifikasi input (persfektif ekonomi) dan tiga tipe kegiatan ekonomi/agribisnis menurut cara produksi (persfektif sosiologi), Bayu Krisnamurti mengusulkan suatu matriks bersel sembilan yang menunjuk pada kemungkinan sembilan pola kegiatan ekonomi pertanian sebagai berikut: Cara Produksi A.Subsistem B.Komersialis C.Kapitalis Faktor Produksi A.1 B.1 C.1 Modal A.2 B.2 C.2 Inovasi A.3 B.3 C.3 Kualifikasi Input Menurut Harianto (2010) tiga tipe ideal agribisnis menurut matriks tersebut adalah : 1. Tipe A.1 : subsistem berbasis faktor produksi 2. Tipe B.2 : komersialis berbasis modal 3. Tipe C.3 : kapitalis berbasis inovasi Tetapi dalam realitas, khususnya di Indonesia kini, sangat mungkin ditemukan dua tipe non ideal, yang sangat mungkin juga akan berkembang menuju tipe ideal. Kalau tidak, sebaliknya justru mengalami stagnasi, yaitu : 1. Tipe B.1 : komersial berbasis faktor produksi 2. Tipe C.2 : kapitalis berbasis modal Salah seorang ilmuwan yang banyak memberikan kritikan, Prof.Mubyarto, khawatir bahwa penerapan paradigma agribisnis hanya akan menguntungkan pengusaha besar saja dan dianggap akan merugikan petani, khsusnya petani kecil (Rahmat Pambudy, 2010). 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan studi pendahuluan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kanjilo Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena pesatnya pergeseran pemilikan lahan sebagai konsekuensi pembangunan desa dan mobilitas petani bekerja di sektor non pertanian. Populasi penelitian adalah semua petani kecil yang tinggal di desa penelitian. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive. 305 Pengumpulan data menggunakan observasi participant, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pada kegiatan observasi yang diamati antara lain keadaan lingkungan persawahan, struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Kegiatan wawancara dilakukan kepada petani, tokoh masyarakatserta perangkat birokrasi desa 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Secara administrasi, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Disebelah utara, berbatasan dengan Desa Tamanyyeleng.Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakkabba Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar.Disebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Makassar.Disebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong. Kecamatan Barombong berbatasan langsung dengan kabupaten Takalar dan kota Makassar. merupakan tempat strategis pembangunan perumahan dan peredaran hasil bumi di Kecamatan Barombong. Desa Kanjilo secara umum kondisi lahanya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa tanaman padi, palawija, maupun tanaman jangka panjang. Aspek sumber daya alam di Desa Kanjilo yaitu (1) Adanya sungai yang membagi dua Desa Kanjilo yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura. (2) Ada air irigasi tanah yang tersebar disetiap dusun dan dapat mengairi areal persawahan. (3) Sebagian areal persawahan dijadikan areal perumahan sehingga lahan pertanian menyempit yang mengakibatkan produksi pertanian menurun. (4) Pekarangan warga sebagian besar masih luas yang dimanfaatkan untuk tanaman sayuran. Di Desa Kanjilo berlangsung dengan pesat modernisasi pertanian. Petani dalam aktivitas usahataninya menggunakan berbagai alat mekanis, seperti traktor tangan dan mesin panen. Selain itu, teknologi kimiawi biologis seperti penggunaan bibit unggul/VUTW, pupuk pabrik serta pestisida. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa di desa ini berlangsung apa yang disebut Harianto (2010) sebagai komersialis berbasis modal. Pada setiap awal pengolahan lahan, petani kecil mempunyai kebiasaan mengambil kredit di Bank. Berdasarkan rumusan hasil sensus menggunakan 13 indikator lokal desa yang disusun melalui musyawarah pngambilan keputusan dengan mengutamakan peran perempuan, kaum muda, orang miskin dan yang termarginalkan diperoleh tingkatan kategori kesejahteraan masyarakat Desa Kanjilo sebagai berikut: Tabel 1. Hasil Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (pkm) di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Kategori Tingkat Kesejahter aan Kanjil o Tangnggal a Bontomana i Camb a Cilallang Kaya 2 5 9 4 2 9 31 1,71 Sedang 85 199 103 151 34 148 720 39,82 Miskin 122 209 106 106 79 127 749 41,42 Z Bilaji % KK 306 Sangat Miskin 85 38 44 81 35 25 308 17,03 Total 204 451 262 242 150 309 1808 10n 0 Sumber : Data Sekunder Hasil Sensus (KPM) Desa Kanjilo 2015 Hasil observasi di Desa Kanjilo menegaskan pesatnya proses konversi lahan, ini karena posisi desa yang berbatasasan langsung dengan Kota Makassar. Alihfungsi lahan dari sawah menjadi perumahan ini menjadi pemandangan utama di Desa Kanjilo. Faktor yang melatarbelakangi petani melakukan alihfungsi lahan adalah faktor ekonomi. Petani kecil mengkonversi lahan karena kebutuhan menikahkan dan sekolah anak, setelah menjual lahan sawahnya kemudian karena tidak menggarap sawah lagi sekarang berwiraswata. Faktor lain yang mendorong konvesi lahan adalah harga tanah yang semakin mahal. Di Desa Kanjilo harga tanah mencapai Rp.800.000-Rp.900.000 rupiah m2. Bahkan jika lahan tersebut berada di dekat lokasi perumahan maka harga yang ditawarkan pengembang dapat mencapai Rp.900.000-1.800.000 m2. Padahal 5 tahun yang lalu masih berkisar Rp.300.000-Rp.400.000 m2. Petani pemilik leluasa menjual lahan dengan harga tinggi, padahal lahan sawah tersebut sangat produktif karena panen bisa dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Aparat desa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan laju konversi, apalagi para pengembang dan makelar tanah (calo) terus menggoda. Petani pemilik yang menjual lahan sawahnya kemudian mengalokasikan untuk membeli lahan yang lebih murah di tempat lain tidak jauh dari Desa Kanjilo sebagai investasi. Sebagian besar lahan sawah di Desa Kanjilo dimiliki pihak swasta dan orang-orang yang tinggal di luar Kecamatan Barombong. Lahan yang belum dijadikan perumahan tetap digarap oleh petani dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan biasanya adalah 1/3 dari hasil diberikan kepada pemilik lahan dan 2/3 sisanya untuk petani penggarap. Namun petani penggarap ini siap-siap mencari lahan garapan baru jika pemilik memutuskan membangun perumahan di lahan tersebut. Alihfungsi lahan sawah mulai terjadi pada kisaran waktu sekitar tahun 1980-an. Konversi lahan ini pada dasarnya dapat terjadi secara sukalera dan karena terpaksa. Petani biasanya terpaksa mengalihfungsikan lahannya karena kondisi wilayah. Adanya pembangunan perumahan di sekitar lahan pertanian menyebabkan terhalangnya saluran irigasi. Akibatnya pengairan sawah jadi terganggu yang pada akhirnya akan merugikan petani. Temuan pendahuluan iniseirama dengan penelitian yang dilakukan Listia dan Sarjana (2015) yang menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan alihfungsi lahan yakni rendahnya pendapatan usahatani padi, pemilik lahan bekerja di sektor luar pertanian, harga lahan, adanya keinginan mengikuti prilaku lingkungan sekitar dan keinginan membuka usaha disektor luar pertanian. Tabel 2. Kecenderungan Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Jenis Jumlah Tangngall Bontoman Cilallan Kanjilo Camba Bilaji a ai g Pekerjaan KK 307 Buruh Harian 119 170 63 154 35 44 585 Wiraswasta 47 51 13 94 5 136 346 Petani Pemilik 27 46 30 29 6 36 174 Tukang Batu 22 30 40 3 48 9 152 Jualan 25 64 28 11 16 3 147 Petani Penggarap - 26 14 7 23 - 70 PNS 9 17 4 21 6 10 67 Sopir 9 6 11 11 3 4 44 Sekuriti 6 - 20 5 - - 31 Tukang Kayu 3 17 5 3 - - 28 Sumber : Data Sekunder Hasil Sensus (KPM) Desa Kanjilo 2015 Konversi lahan pertanian menjadi perumahan juga membawa berbagai perubahan jenis pekerjaan petani di luar sektor pertanian. Kecenderungan bekerja diluar sektor pertanian didominasi sebagai buruh harian dan berwiraswasta. Pekerjaan sebagai buruh harian biasanya petani menjadi buruh bangunan. Adanya perumahan juga membuka lapangan kerja menjadi sekuriti di perumahan tersebut. Kombinasi pekerjaan bagi warga sekitar juga diamati aktivitas wanita tani yang bekerja sebagai tukang suci, tukang setrika dan pembantu rumah tangga di perumahan yang ada di Desa Kanjilo. Diantara 6 dusun maka Dusun Bilaji yang paling pesat pembangunan perumahannya. Rata-rata pemilik perumahan tersebut berasal dari Kota Makassar. Untuk membantu ekonomi keluarga wanita tani juga memanfaatkan pekarangan rumah.Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga jika dikelolah dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga seperti bahan pangan atau bahan obat-obatan. Faktor pendukung dari pemanfaatan lahan pekarangan tersebut adalah adanya partisipasi dari wanita tani. Di Desa Kanjilo, petani kecilmenganggap pemanfaatan lahan pekarangan ini tidak menimbulkan kerumitan bahkan menjadi pekerjaan sampingan. Pengamatan menunjukkan bahwa jenis tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh wanita tani Desa Kanjilo adalah tanaman sayuran, seperti kankung, terong, kemangi, pare, pare belut, talas, kacang panjang.Pemanfaatan lahan pekaranganselain dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang mana sebelumnya mesti membeli sayuran di pasar.Bahkan jika dimanajemen dengan baikmenjadi strategi untuk menambah pendapatan keluarga. Adapun jika dijual hasil dari lahan pekarangan tersebutbisadiperoleh sekitar Rp.50.000-Rp.200.000 per dua bulan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cepriadi dan Yulida (2012) bahwa program pemanfaatan lahan pekarangan sangat menguntungkan baik dari segi konsumsi maupun dari segi ekonomi. 308 5. KESIMPULAN Modernisasi pertanian menunjang keberhasilan sektor pertanian berhadapan dengan kecenderungan konversi lahan di Desa Kanjilo. Alihfungsi lahan menyebabkan petani mencoba alternatif bekerja diluar sektor pertanian. Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi strategi petani kecil menambah pendapatan keluarga secara berkesinambungan. 6. DAFTAR PUSTAKA Amaluddin, M. 1987. Kemiskinan dan Polarisasi Sosial. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. Andi Nuhung, Iskandar. 2006. Bedah Terapi Pertanian Indonesia. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. Cepriadi dan Yulida, Rosa. 2012. Persepsi Petani terhadap Usahatani Lahan Pekarangan. Indonesian Journal of Agricultural Economics. Vol.3 No.2 Desember 2012. Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Penerbit Bhrata Karya Aksara. Jakarta. Kompas (03/12/2013). Jumlah Petani Menyusut. Halaman 18. Jakarta. Listia Dewi, Ida Ayu dan Sarjana, I Made. 2015. Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah menjadi Lahan Non Pertanian. Jurnal Manajemen Agribisnis. Vol.3 No.2 Oktober 2015. Syahyuti. 2013. Pemahaman terhadap Petani Kecil sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol.31 No.1 Tahun 2013. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Penerbit Alfabeta. Bandung. Triyono, L dan Nasikun. 1992. Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa. Penerbit Rajawali Press bekerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Yogyakarta. 309 STRATEGI PENGHIDUPAN WARGA DUSUN BONTO DI KAWASAN HUTAN PINUS, DI KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN Sityi Maesarotul Qori’ah Agrarian Resources Center (ARC) Bandung E-mail: [email protected] dan [email protected] Abstrak Penunjukkan kawasan hutan di Indonesia merupakan salah satu alat perebutan sumbersumber penghidupan rakyat. Salah satunya di dusun Bonto. Dikeluarkannya SK Menteri Pertanian 1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, menjadikan kawasan dusun Bonto menjadi kawasan hutan lindung. Secara legal, warga di sekitarnya menjadi tidak bisa mengakses wilayah tersebut, padahal sebelumnya warga menguasai lahan dan mengelolanya menjadi sumber mata pencaharian. Kawasan tersebut ditanami pohon Pinus Merkusii yang menurut para ahli adalah tanaman yang dapat merusak kondisi tanah di sekitarnya, khususnya untuk lahan pertanian. Sejak tahun 1980-an ketergantungan warga akan padi semakin meningkat, namun daya dukung lingkungan semakin menurun sejak 2010, menurunnya produktivitas tanaman tersebut disebabkan karena berkurangnya persediaan air di wilayah karena keberadaan hutan pinus. Tulisan ini akan menguraikan tentang strategi warga dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan pangannya di tengah-tengah semakin hilangnya daya dukung lingkungan di lahan pertaniannya. Temuan lapangan menjelaskan bahwa terdapat strategi-strategi warga untuk beradaptasi dengan lingkungannya, serta peran kelembagaan akibat perubahan relasi diantara mereka, karena perubahan lingkungan, untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode Riset Aksi Partisipatif ini berlangsung pada akhir 2015. Pendekatan dan teori tentang hubungan manusia dan lingkungan serta peran kelembagaan dan relasi sosial di masyarakat membantu mempertajam analisis dalam tulisan ini. Kata Kunci: Relasi Sosial, Kelembagaan, Hutan Pinus, Daya Dukung Lingkungan Abstract Designation of forest area in Indonesia is one of instruments for seizing people livelihood resources. One of them happened in Bonto village, since the Ministry of Agriculture Decree 1982 promulgated on Forest Area Designation, which the Bonto area has become protected forest area. Legally, local people could access the area, meanwhile previously they hold and control the land for source of their live. The area was planted with pines (Pinus Merkusii) that according to experts as a tree that possibly could affect land fertility, especially for agriculture land. Since 1980s people dependence of paddy has increased, however, its environmental capacity has decreased since 2010 marked by declining of paddy productivity because running out of water supply due to existing of pine forest. This paper explains about people strategy time by time for fulfill the need of food in the mid of getting loose of environmental capacity for agriculture land. Field findings depict that there are various strategies conducted by people in order to adapt with their environment, as well as role of institution effected by relations change within the community, due to environment change, to support their live. This research used Participatory Action Research (PAR) method that conducted in 2015. Approaches and theory on human and environment relation as well as role of institutions and social relation has been sharpening the analysis in this paper. Keywords: Social Relation, Institutions,Pine Forest, Environment Capacity 310 1. PENDAHULUAN Dusun Bonto34 merupakan salah satu dusun di desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kompang terletak 30 km sebelah barat Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemukiman warga didominasi lereng-lereng dengan kemiringan 30-70 derajat dengan ketinggian 400-700 mdpl. Sebelum menjadi desa, dahulu Kompang merupakan peninggalan dari kerajaan kecil yaitu Kerajaan Kompang (senantiasa menjalin kerjasama dengan Kerajaan Gowa Tallo), sehingga berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakatnya mirip dengan kebiasaan Kerajaan Gowa Tallo. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan berada dalam kondisi tidak stabil.Kisruh politik yang terjadi di Sulawesi Selatan salah satunya adalah pemberontakan yang di pimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Pemberontakan yang dilakukan secara berkelompok (gerombolan atau gerilya35) dan tinggal bersama-sama di satu tempat untuk menghindari dari serangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu tempat yang dipilih oleh segerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar adalah dusun Bonto. Dusun Bonto menjadi salah satu tempat atau markasnya pasukan gerilya.Warga setempat dan pasukan Qahhar Mudzakkar biasa menyebutnya gurilla, yang berarti gerombolan (Salim & Ni'am, 2012, p. 23). Gerilyawan bersembunyi di satu tempat penting bagi masyarakat Dusun Bonto, Pattontongan (berarti jendela). Sepeninggal gurilla, tahun 1980-an, pemerintah setempat mengalihfungsikan hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat. Sehingga memantik konflik antara masyarakat dan pemerintah (hanya sebagian orang yang mendapat keuntungan dari adanya hutan), sedangkan masyarakat setempat dipinggirkan untuk memanfaatkan dan mengelola hutan.Itu pun yang terjadi dengan masyarakat dusun Bonto. Warga tidak tahu serta tidak dilibatkan dalam proses penunjukkan sebagian wilayah dusun Bontoyang kemudian menjadi kawasan hutan. Warga hanya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mengakses kawasan hutan. Dinas Kehutanan setempat secara sepihak kemudian menanami kawasan hutan dengan Pinus. Setelah ditanami pinus tahun 1984, kurun waktu 31 tahun sumber mata air warga pun banyak yang hilang, karena diserap oleh pinus yang sebenarnya tidak cocok ditanam di kawasan hutan produksi, di wilayah dengan lereng 450, serta di wilayah dengan curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Wilayah yang kemudian ditunjuk menjadi kawasan hutan, semestinya dikelola berdasarkan hak-hak warga setempat, bukan hanya berdasarkan penetapan kawasan hutan yang kemudian menjadi hutan negara sebagaimana praktek warisan kolonial yang masih hidup hingga saat ini. Wilayah yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan di Indonesia kenyataannya sedikit yang benar-benar kawasan hutan. Tanah yang diklasifikasikan kawasan hutan merupakan tanah yang tidak terdaftar sebagai tanah pertanian, sehingga mengabaikan tata guna tanah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat (Contreras, Hermosilla, & Fay, 2006). Jauh sebelum dikeluarkan SK penunjukan hutan di dusun Bonto, muncul program revolusi hijau tahun 1970-an, berdasarkan program ini tanaman lokal warga digantikan dengan tanaman jangka panjang. Revolusi hijau diperkenalkan untuk menciptakan tingkat produksi dalam sektor pertanian. Kemudian, dimaksudkan untuk menghindari konflik agraria di negara-negara berkembang. Namun realitanya, revolusi hijau kemudian memantik konflik terbuka agraria di sejumlah negara yang mengimpelentasikan dari revolusi hijau ini. Salah satu program dari revolusi hijau adalah pembagian benih dengan kriteria bibit unggul untuk jenis tanaman yang ditanam dalam luasan yang sangat luas dan 34 Bonto dalam bahasa Konjo (bahasa asli yang digunakan oleh warga Dusun Bonto) berarti dahi yang menonjol.Bonto digambarkan dengan dahi atau jidat karena kontur wilayah dusun Bonto serupa dengan dahi manusia. 35 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerilya adalah cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba). 311 ditanam selama berpuluh-puluh tahun, namun kemudian menimbulkan munculnya hama (Tim Konphalindo, 2001, p. 134 dan 136). Warga dusun Bonto pun kena imbas dari program ini, cengkeh dan kakao kemudian menggantikan tanaman utama warga, yaitu jagung. Dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pada Bab III Pasal 10, urusan pengurusan hutan bertujuan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan dijadikan oleh warga sebagai tempat berladang (baik dengan izin ataupun tanpa izin), aktivitas penebangan kayu hutan oleh warga (dalam jumlah besar ataupun kecil), hutan sebagai investasi dan menyimpan harta, hutan sebagai kehidupan dan warga menggantungkan hidup dari hasil hutan (dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan) (Santoso, 2004). Banyak studi dan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti mengenai kawasan hutan pinus di Kabupaten Sinjai. Namun, dari semua penelitian itu tidak ada sama sekali yang memfokuskan pada bagaimana sebenarnya warga di dusun Bonto bisa bertahan di tengah-tengah kawasan hutan pinus yang sebenarnya sangat merugikan bagi warga dusun Bonto. Penelitian yang dilakukan oleh kebanyakan peneliti, hanya sebatas membahas bagaimana cara kerja pinus dalam mengambil sumber penghasilan warga (Tim Peneliti Payo-payo, 2015). Hasil penelitian lainnya, hanya sebatas bagaimana pinus bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan bagi warga. Selain itu juga, bagaimana pinus bisa menjadi penyebab bencana longsor di Kabupaten Sinjai tahun 2006 (Salim & Ni'am, 2012). Penelitian lainnya adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai terkait alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi dengan ditanami pinus, lagi-lagi penelitian ini hanya sebatas melihat dari aspek hukum dan aturannya saja, sedangkan warga setempat yang terkena imbas dari kebijakan tersebut tidak mendapat perhatian lebih (Irfan F, 2014). Lainnya adalah penelitian yang menjelaskan bagaimana bencana yang tercipta di dua desa di Sulawesi Selatan (salah satu desa yang diceritakan adalah Desa Kompang), kajian yang dilakukan berhenti pada penelusuran mengenai proses terbentuknya suatu bencana di desa tersebut. Penelitin dilakukan dengan tujuan agar memberikan informasi yang akurat serta sebagai upaya untuk menaggulangi resiko bencana. Hanya berhenti disitu saja, sedangkan bagaimana warga di desa tersebut bisa bertahan dan terus berjuang hidup di atas tanah yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sosialnya tidak banyak dibahas (Sirimorok, Batiran, & Sanusi, 2014). Karena itu tulisan ini menjadi sangat penting, karena dari berbagai kajian yang sudah ada, tulisan ini akan melengkapinya dengan ulasan tentang bagaimana strategi warga dusun Bonto dapat bertahan hidup di kawasan hutan pinus? Bagaimana cara warga beradapatasi dengan kondisi dan daya lingkungan yang semakin tidak mendukung untuk kegiatan pertanian warga karena keberadaan pinus? Sementara sumber daya air semakin berkurang karena pinus telah menghisap sumber air mereka. Sedangkan air merupakan hal yang sangat penting untuk dapat terus berproduksi. Tulisan ini sekaligus ingin menjawab sisi lain dari pinus yang merugikan warga yang berada di kawasan hutan yang ditanami pinus. Pemecahan masalah yang muncul dari warga sendiri adalah adanya keinginan untuk mengganti pinus dengan tanaman yang bisa menghasilkan dari sisi ekonomi untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Yaitu, dengan menggantinya dengan tanaman jangka panjang misalnya pala, cengkeh. Termasuk juga akan dapat menjawab beberapa hal yang luput dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tentang keberadaan warga sekitar yang belum mendapat perhatian banyak. 312 2. KERANGKA TEORITIS Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kerangka teori yang digunakan untuk menjawab atas pertanyaan penelitian dalam paper ini. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini. Hubungan Manusia dan Lingkungan Manusia dan lingkungan memang haruslah dapat menyesuaikan diri (adaptasi). Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan cepat dimanapun mereka berada, di lingkungan apapun. Karena itu merupakan cara mereka untuk bertahan hidup. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan keduanya saling berhubungan. Manusia dalam hal ini adalah sebagai fenotipe, yang merupakan perwujudan dari apa yang dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan. Permasalahan dalam lingkungan hidup adalah adanya hubungan manusia dan lingkungannya. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang berkuasa di bumi ini. Ia hanya menjadi sosok penentu lingkungan dengan tujuan agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Adanya anggapan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang paling berkuasa di bumi adalah anggapan yang salah. Apalagi, jika ia menjadi sosok yang malah merusak lingkungan di sekitarnya. Idealnya, antara manusia dan lingkungan merupakan satu makhluk dengan makhluk lainnya yang mempunyai hubungan timbal balik (Soemarwoto, 1997). Konsep manusia dan lingkungannya sering memicu terjadinya konflik. Salah satunya adalah aspek kependudukan dan aspek kelangkaan sumber daya lingkungan. Aspek kependudukan berkaitan erat dengan sekumpulan manusia yang sudah tinggal dan hidup berpuluh-puluh tahun lamanya di lingkungannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu sekumpulan manusia tersebut dihadapkan dengan konflik yang melibatkan lingkungan yang mereka tinggali. Mereka dibenturkan dengan regulasi yang membatasi mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitarnya. Tanah-tanah mereka dirampas atas dalih pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tanah-tanah dialih fungsikan dengan tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di tanahnya. Dan yang terjadi adalah masyarakat setempat pun tidak bisa tinggal diam ketika tanah yang selama ini mereka tinggali dirampas atas kepentingan sepihak, baik itu yang melibatkan pemerintah setempat maupun kepentingan bisnis. Dari sudut pandang lain dapat dilihat bahwa telah terjadi konflik antara masyarakat yang merasa dirugikan atas regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang telah mengambil sumber daya alam dan lingkungannya. Masyarakat mempertahankan lingkungannya yang telah memberikan kehidupan berpuluh-puluh tahun bagi mereka (Li, 2012). Dalam kaca mata Sosiologi, konflik dalam hal ini merupakan hal yang wajib, karena konflik merupakan proses sosial untuk menyatukan masyarakat. Aspek kelangkaan sumber daya lingkungan dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak semua memahami mengenai regulasi dan kebijakan-kebijakan yang akhirnya merugikan mereka. Selain kehilangan sumber daya alam, mereka pun perlahan-lahan akan kehilangan sumber penghidupannya. Penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Karena itu, relasi antara manusia dengan lingkungan, pada perkembangannya, sering menimbulkan konflik. Isu yang mengemuka adalah konflik yang berkaitan dengan tanah, air ataupun udara. Misalnya konflik yang berkaitan dengan tanah adalah banyaknya kelompok-kelompok petani yang harus rela meninggalkan kebunnya karena lahannya telah ditetapkan sebagai lahan perkebunan skala besar yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan maupun pemegang konsesi kehutanan (baik swasta maupun BUMN). Sejumlah perangkat hukum dirumuskan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Negara, untuk membangun legitimasi proses tersebut. Untuk kasus Indonesia, sejumlah kawasan tersebut akan diubah terlebih dahulu statusnya menjadi Tanah Negara sebelum didistribusikan kepada pemegang hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Hal 313 ini didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan sebuah kawasan sumberdaya alam (kebun maupun hutan) yaitu mencapai peningkatan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. PeranKelembagaan Lembaga dalam pengertian yang berhubungan dengan kawasan hutan adalah semua aturan baik formal maupun in-formal yang digunakan oleh masyarakat di satu wilayah yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Tentunya sangat berkaitan dengan aturan yang berlaku, yang dipakai oleh masyarakat setempat dan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Sehingga, kedua aturan ini dapat saling melengkapi. Bukan saling membunuh satu sama lain. Apalagi, malah memantik konflik diantara keduanya (Suciati, Anggoro, Ristanto, & dkk, 2007). Kelembagaan yang ada di Indonesia untuk mengatur hubungan manusia dan lingkungan sudah ada sejak masa kolonial. Baik itu lembaga resmi negara ataupun lembaga-lembaga yang hidup secara alamiah di masyarakat, termasuk organisasi non pemerintah (ORNOP) dan lainnya, yang semuanya memiliki tujuan tertentu untuk memperbaiki sumber daya yang ada di bumi nusantara. Akan tetapi, ada juga yang terkadang hanya utopia belaka. Adanya kelembagaan berperan untuk mengatur dimensi kehidupan bermasyarakat. Dalam bahasa Foucault dikenal dengan pengaturan yang bersifat rasional, dimana proses yang dilalui merupakan jalan untuk mencapai perbaikan kehidupan manusia. Peran pemerintah dalam mengelola masyarakat salah satunya adalah dengan penetapan lokasi-lokasi pemukiman masyarakat agar efisien dan lebih dekat dengan lokasi administratif. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia awalnya tinggal di pegunungan, namun kemudian dipindahkan dengan alasan kemudahan pelayanan administratif tersebut. Namun, terkadang kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan tata cara kehidupan masyarakat lokal. Alasan lain adalah dengan bertambahnya populasi manusia yang mengharuskan pemindahan pemukiman yang baru (Li, 2012). Pemukiman warga yang baru bukannya memberikan rasa aman terhadap masyarakat, namun kemudian yang terjadi adalah masyarakat menjadi rentan terhadap bencana, baik itu bencana alam maupun bencana kelaparan. Dengan demikian, dari sisi peningkatan kualitas hidup masyarakat, kebijakan pemerintah tersebut dinilai gagal, karena tidak melihat kondisi sosial masyarakat dengan lingkungannya. Berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan, peran kelembagaan negara telah membatasi ruang gerak dan akses masyarakat atas sumber daya alam di lingkungannya. Berbeda halnya dengan peran kelembagaan lokal, dimana di sejumlah pengalaman mampu membuat pengaturan yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Pengaturan yang dibuat oleh masyarakat setempat yang dilembagakan tersebut dibuat untuk upaya adaptasi kehidupan mereka untuk tujuan kehidupan bersama. Keberadaan kelembagaan lokal pun dapat menciptakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat, karena bersumber pada otoritas kultur tradisional yang sekaligus juga merumuskan mekanisme pemantauan dan memperbaiki setiap aturannya jika dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, peran kelembagaan yang berada di desa itu pula dapat menjamin kelangsungan hidup warganya. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dijelaskan bahwa pemerintahan desa dalam hal pengaturan pemerintahan desa harus berlandaskan pada keanekaragaman, otonomi lokal yang berbasis untuk pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Safitri, 2000). Dalam UU No. 22 tahun 1999, UU itu dengan tegas memberikan kebebasan kepada kepala desa dalam mengatasi konflik yang terjadi. Dalam hal ini, terkait konflik akibat adanya kawasan hutan pinus yang menurut warga Dusun Bonto merugikan bagi sumber mata penghasilan mereka. Kepala desa juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan 314 konflik yang terjadi yang kemudian dibantu oleh lembaga adat setempat. Sumber otoritas desa pula didukung oleh hak asal-usul desa (Safitri, 2000). Salah satu lembaga lokal yang ada di Dusun Bonto adalah hadirnya salah satu tarekat keagamaan, yaitu Khalwatiyah Samman. Bukan hanya itu, tokoh agama dari tarekat itu pun menjadi salah seorang warga yang sangat dituakan di dusun Bonto. Hampir seluruh warga di desa Kompang pun menghormati tokoh tersebut. Bahkan dalam proses penolakan kehadiran pinus pun tokoh inilah yang menggerakan warga lainnya untuk melakukan penolakan. Hadirnya tokoh masyarakat bahkan tokoh agama di salah satu desa dengan sisi lain mempunyai kharismatik dan dapat menggrekan warga dengan rasa patuh terhadap tokoh tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun kelembagaan masyarakat setempat. Ini bisa dijadikan sebagai basis pengorganisasian dan sebagai upaya untuk memperkuat lembaga lokal (Suciati, Anggoro, Ristanto, & dkk, 2007). 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu sejak 28 September – 22 November 2016.Tempat penelitian adalah di Dusun Bonto, Desa Kompang, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian aksi partisipatif (Partisipatory Action Research/PAR). Pendekatan PAR merupakan pendekatan penelitian dengan lebih menitik beratkan pada partisipasi peneliti yang kemudian ia hanya menjadi ‘pendamping’ peneliti saja, sedangkan yang menjadi peneliti utama adalah masyarakat itu sendiri yang pada metode penelitian lain adalah yang menjadi objek penelitian. Adapun dalam pengertian lain, PAR adalah salah satu metode penelitian yang digunakan secara partisipatif antara peneliti dengan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mendorong dan penguatan masyarakat setempat agar terciptanya aksi-aksi yang transformative serta pada akhirnya dari aksi-aksi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pada level pemerintahan yang lebih tinggi, karena dengan metode PAR, hasil penelitian kemudian adalah berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang dialami oleh masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam penggunaan metode PAR ini, ada beberapa teknik yang digunakan guna mendapat informasi dan data yang sangat akurat. Di antaranya adalah sebagai berikut: Transek Transek adalah teknik penelusuran lokasi penelitian, yaitu melakukan pengamatan langsung terkait objek penelitian (landskap – bentang alam) secara keseluruhanuntuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian secara keseluruhan.Teknik ini memungkinkan keterlibatan masyarakat penuh karena seperti yang diuraikan oleh Moeliono dan Djohani (1996) masyarakatlah yang lebih mengetahui kondisi alam di lingkungannya. Pada pelaksanaannya, kira-kira 15 orang warga Dusun Bonto terlibat dalam kegiatan ini. Wawancara Selain transek, proses pengumpulan data dilakukan pula dengan melakukan wawancara kepada masyarakat di Dusun Bonto, Desa Kompang. Wawancara dengan masyarakat setempat merupakan kegiatan yang sangat penting, karena informasi yang didapatkan berasal dari informan kunci. Informan kunci dalam proses penelitian ini adalah penduduk di Dusun Bonto yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat dan penduduk yang berlatar belakang keluarga petani di Dusun Bonto. Wawancara dilakukan kepada 10 narasumber, yaitu Kepala Desa Kompang, Kepala Dusun Bonto, tetua salah satu tarekat di Dusun Bonto. Selain itu, melakukan wawancara kepada beberapa warga dusun Bonto, yaitu Ibu Suryani, Pak Hasyir, Pak Anwar, Pak Asikin, dan dg. Unding. Mengapa wawancara dilakukan? Karena untuk mendapatkan informasi dan 315 data yang lebih akurat dan komprehensif. Dari wawancara ini, peneliti mendapatkan ceritacerita berdasarkan penuturan langsung dari masyarakat setempat. 4. PEMBAHASAAN DUSUN BONTO, SUMBERDAYA ALAM DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai dua hal yang menjadi bagian penting dalam hasil temuan selama penelitian. Dalam bagian ini pula terdapat dua bagian pembahasan, yaitu potensi sumber daya alam di Dusun Bonto dan hutan pinus serta perlawanan rakyat untuk penghidupan. Potensi Sumber Daya Alam di Dusun Bonto Desa Kompang terletak 30 km sebelah barat Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemukiman warga didominasi lereng-lereng dengan kemiringan 30-70 derajat dengan ketinggian 400-700 mdpl. Pada bulan September hingga akhir November 2015, iklim desa Kompang, khususnya dusun Bonto bersuhu 24oC pada malam hari dan 30oC pada siang hari. Dusun Bonto berada di ketinggian sekitar 478 mdpl. Dusun Bonto terletak di sekitar garis lintang: S 5,233941° dan garis bujur : E 120.119038°. Sebelah Utara Desa Kompang berbatasan dengan Desa Pattongko.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saontare (lihat Peta 1). Gambar 1. Peta Desa Kompang Sumber: (Kompang, 2015) Tahun 1950-1975, warga Desa Kompang menanam jagung di lahan-lahan kebunnya. Jagung menjadi makanan pokok warga. Tidak hanya warga Desa Kompang saja yang mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok, warga di Desa Gantarang (sebelum 2006 merupakan bagian dari Desa Kompang) juga demikian (Salim & Ni'am, 2012). Hal ini juga dituturkan Pak Ansar, masih jelas dalam ingatannya pada saat itu, bahwa sejauh mata memandang yang terlihat di kebun-kebun warga adalah tanaman jagung. Ia menambahkan bahwa apabila musim kemarau tiba, sesuai dengan cara bertani nenek moyangnya dahulu, kebun jagung yang akan ditanami kembali tidak dicangkul, namun dibakar.36 Selain komoditas pertanian untuk tanaman pangan, wilayah ini juga sumber komoditas perkebunan dan hasil hutan. Komoditas kebun utama sejak tahun 1950 adalah kopi, sebelum kemudian cengkeh menjadi sumber ekonomi warga hingga saat ini, 36 Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015. 316 sementara aren (bahan utama pembuatan gula merah) adalah komoditas hasil hutan yang masih terus bertahan hingga saat ini, meskipun tidak banyak petani yang menanam aren dan mengolahnya menjadi gula merah. Hal ini menggambarkan kondisi alam yang memadai untuk kehidupan ekonomi warga serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa komoditas utama warga di Dusun Bonto serta dinamikanya dari tahun ke tahun. 2011-…. 20062010 20012005 19912000 19811990 19711980 19611970 Komoditas 19501960 No. <1950 Tabel 1. Sejarah Perkembangan Komoditas di Desa Kompang Tahun Pertanian 1 Padi ••• ••• ••• ••• ••• ••• 00 2 Jagung ••• ••• ••• 00 00 00 0 0 Perkebunan 3 Cengkeh ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4 Kakao ••• ••• ••• 00 00 5 Kopi ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6 Kemiri ••• ••• ••• 00 00 0 0 0 7 Pala 00 00 ••• ••• 8 Kelapa ••• ••• ••• ••• ••• ••• 00 00 Hasil Hutan 9 Aren ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 10 Langsat ••• ••• ••• ••• ••• ••• 00 00 11 Manggis ••• ••• ••• ••• 12 Rambutan ••• ••• ••• ••• ••• ••• 00 00 13 Durian ••• ••• ••• ••• 00 00 00 00 Sumber: Forum Group Discussion (FGD) bersama petani di Desa Gantarang, pada17 Oktober 201537 Keterangan: •••: Sangat banyak, 00: Kurang, 0: Sangat Kurang Komoditas Utama di Dusun Bonto Komoditas baru yang masuk ke desa Kompang adalah cengkeh. Cengkeh masuk pada era 1971-1980, hingga sekarang hasil panen cengkeh terhitung sangat banyak. Meskipun, beberapa petani cengkeh mengeluhkan bahwa pohon cengkehnya tahun ini banyak yang mati, kering dan hasil panennya berkurang, tanaman ini tetap menjadi sumber penghasilan utama warga hingga saat ini. Hampir setiap petani di dusun Bonto memiliki pohon cengkeh, baik itu yang ditanam di pekarangan rumah ataupun di kebun-kebun di sekitar gunung Pattontongan (termasuk di kawasan hutan pinus). Masa awal penanaman cengkeh, petani yang ingin menanam cengkeh membeli benih cengkeh di Kepala Desa Pak Hodde. Namun, kini tidak semua petani di dusun Bonto membeli benih cengkeh. Sebagian besar petani membudidayakan benih cengkehnya sendiri. Jika pun ingin membeli benih 37 Sejarah komoditas yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil FGD dengan beberapa warga di Desa Gantarang, yang dilakukan oleh Tim Gantarang pada proses Pelatihan Penelitian Desa SRP Payo-Payo.Data ini juga berlaku di Desa Kompang karena memiliki persamaan sejarah komoditas di masing-masing desa.Mengingat Desa Gantarang merupakan desa pecahan dari Desa Kompang. 317 cengkeh kepada petani lain yang biasa menjual benih cengkeh dijual dengan harga Rp 5.000 per satu pohon benih cengkeh. Sejak diperkenalkannya cengkeh, warga dusun Bonto mengelola cengkeh dan menjadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun demikian, mereka masih tetap menanam tanaman aren, kemiri dan jagung. Pada masa pemerintahan Pak Hodde (Kepala Desa tahun 1966-1981), pemerintah membagikan 4.000 bibit cengkeh untuk ditanam di kebun warga. Masing-masing keluarga mendapatkan bibit dengan harga Rp 25 – Rp. 250 per bibit38 (Salim & Ni'am, 2012, p. 28). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi pemasok cengkeh nasional. Kabupaten Sinjai, dimana dusun Bonto berada salah satu wilayah yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan nasional industri yang menggunakan bahan baku cengkeh. Corak produksi yang memungkinkan komoditas ini dikelola dalam skala kecil atau rumah tangga, memungkinkan komoditas ini menjadi andalan setiap keluarga untuk menopang kehidupan sehari-harinya dan masa depan keluarganya. Awal penanaman cengkeh di dusun Bonto bersamaan dengan booming nya komoditas ini di pasar domestik dan internasional. Di Indonesia, tahun 1970-an, cengkeh merupakan bahan bakurokok kretek dan menjadi salah satu penyumbang angka pertumbuhan ekonomi negara (EA & dkk, 2013, pp. 21-22). Karena itu, setelah mengalami kegagalan pada masa awal penanaman, warga tetap mencoba menanam cengkeh kembali pada tahun 1977. Salah seorang pelopor tanaman cengkeh di dusun Bonto, yakni Pak Asikin Pella, memberikan pengetahuannya untuk mengelola tanaman cengkeh kepada warga lainnya di sebagian kebun warga yang masih ditanami aren, kemiri dan jagung (EA & dkk, 2013). Hal ini dimulainya cengkeh sebagai komoditas primadona dan sumber penyangga kehidupan warga Desa Kompang, khususnya dusun Bonto. Memasuki era tahun 1980-an, cengkeh di dusun Bonto menjadi salah satu penyuplai industri cengkeh nasional. Di tingkat nasional, luas areal tanaman cengkeh di Indonesia mencapai 400 ribu Ha pada tahun 1980 dan terus meningkat rata-rata sebesar 0,35% pertahun hingga tahun 1997 (V. J. Siagian 2014, 9). Tidak mengherankan jika warga Dusun Bonto pun kemudian menyandarkan sumber ekonominya kepada tanaman cengkeh yang ditanamnya hingga saat ini. Musim panen cengkeh di dusun Bonto adalah pada bulan ke 7-11 (Juli-November). Sebelumnya bulan ke 3 pohon cengkeh mulai berbuah. Bulan September dan Oktober merupakan puncak panen cengkeh. Bulan November hasil panen cengkeh mulai berkurang. Selain cengkeh (tanaman jangka panjang), dari hasil wawancara dengan warga Dusun Bonto, hasil panen tanaman lainnya adalah padi, kakao, jagung, kopi, buah-buahan (manggis, langsat, durian dan rambutan) dan sayur-sayuran (kangkung, sawi, buncis, kacang panjang). Namun, tanaman jangka pendek ini hanya dijadikan tanaman sampingan setelah habis masa panen cengkeh. Hutan Pinus di Dusun Bonto dan Lahan Pertanian Rakyat Kondisi wilayah, khususnya topografi Kabupaten Sinjai merupakan kawasan daratan landai dengan kemiringan 0-45%. Sekitar lebih dari 30%-nya merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan di atas 40% (Irfan F, 2014). Begitu juga kondisi di dusun Bonto, dalam rangka penanaman pohon di hutan, Dinas Kehutanan, pada tahun 1984 memilih benih pinus untuk ditanam di kawasan hutan di wilayah Dusun Bonto. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan penghijauan yang sudah dicanangkan sejak tahun 1976. Secara tekhnis, pemilihan tanaman pinus didasarkan pada kemudahan proses penanamannya. Jenis pinus yang ditanam adalah Pinus Merkusii Jung et de Vriese (Pinus Merkusii). Pinus merkusii merupakan jenis pinus yang tumbuh alami 38 Bergantung pada kondisi bibit yang tersedia, jika sudah tumbuh daunnya, harganya semakin mahal . 318 di di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera (Aceh, Tapanuli, dan Kerinci). Ciri khas dari pohon pinus merkusii adalah pohonnya besar, batang lurus, berbentuk silinder, kulit luarnya kasar, tegakkan dewasa mencapai 45 m dengan diameter 140 cm. Usia pohon pinus yang tumbuh di kawasan hutan dusun Bonto sekisar 31 tahun dan yang paling muda 9 tahun. Bahkan, setelah terjadi bencana longsor tahun 2006, tumbuh beberapa pohon pinus baru dibeberapa titik.Padahal, sebelumnya tidak ditanami pinus. Ciri lain pinus merkusii adalah penyebaran biji yang mudah diterbangkan oleh angin, benih pinus mudah didapat dengan jumlah yang banyak, laju pertumbuhannya cepat, serta dapat tumbuh pada lahanlahan kritis (Tim Peneliti Payo-payo, 2015). Sehingga akan mudah tertanam tanpa perawatan lebih lanjut dan akan segera memenuhi target penghijauan kembali hutan khususnya di kawasan ini (Tim Peneliti Payo-payo, 2015). Sejak saat itu, kawasan hutan pinus di Desa Kompang pun semakin meluas. Terdapat di 3 lokasi39, yaitu di Laiyya dengan lahan seluas 84 Ha, yang saat ini umur pohonnya mencapai 21 tahun, dengan jumlah 35.200 pohon. Kemudian di Kp. Baru dengan total luas lahannya 100 Ha, yang umurnya mencapai 21 tahun sejumlah 40.000 pohon, serta di Buluparingi diatas lahan seluas 164 Ha yang umurnya lebih muda, yaitu 15 tahun, berjumlah 32.000 pohon (Irfan F, 2014). Warga menganggap bahwa kehadiran hutan pinus telah sedikit demi sedikit menghilangkan suplai air di desanya. Hal ini ditandai dengan hilangnya sumber mata air dan debit air sungai yang semakin sedikit dari tahun ke tahun. Pak Hasyir menuturkan bahwa ketika ia berusia 10 tahun (yaitu sekitar tahun 1961), ia masih bisa menangkap kepiting di sungai kecil yang ada di dusun Bonto40. Namun, ketika ia menginjak usia dewasa, ketika pohon Pinus mulai ditanam, ia sulit mendapatkan kepiting di sungai. Pada saat itu, hutan pinus sudah tumbuh besar. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa pinus telah mengambil persediaan air di dusunnya. Berdasarkan penuturan warga lainnya, sebelum ada pinus, air di dusun Bonto sangatlah melimpah.41 Di sisi lain, keberadaan pinus di kawasan hutan negara merupakan upaya pemanfataan sumberdaya alam dengan cara mengundang investor. Setelah pinus bisa besar dan cukup umur untuk dimanfaatkan hasilnya, pemerintah daerah mengundang investor untuk dijadikan sumber pemasukan daerah. Pemerintah kabupaten Sinjai bekerja sama dengan PT. Rakindo untuk bekerja bersama melakukan penjualan getah pinus yang disadap oleh petani. Tahun 2007, ketika warga mulai melakukan penyadapan getah pinus, harga getah pinus saat itu hanya Rp 1.500 per kilogram dan harga yang dianggap terlalu murah ini membuat warga kemudian tidak tertarik lagi untuk menyadap pinus.PT Rakindo kemudian menaikkan harga pembelian getah pinus menjadi Rp 2.000 per kilogram (Salim & Ni'am, 2012, pp. 36-37). Getah pinus tersebut adalah hasil produksi getah pohon pinus yang ditanam di kawasan hutan lindung. Hal tersebut disampaikan oleh Andi Sainal (anggota DPRD Kabupaten Sinjai Dapil Dua) yang menyatakan bahwa hutan pinus atau 39 Lihat kembali Peta 2 untuk melihat posisi lokasi hutan Pinus di Desa Kompang. Wawancara dengan Pak Hasyir pada 16 November 2015 41 Mengenai keyakinan warga bahwa pinus telah mengambil air mereka berdasarkan hasil penelitian Tim Kompang (Pelatihan Penelitian Desa Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo tahun 2015) bahwa keberadaan hutan pinus di dusun Bonto tidaklah layak. Karena pinus dapat mengurangi kandungan air tanah melalui proses intersepsi, evapotranspirasi dan air limpasan (runoff). Bentuk tajuk pohon pinus conifer, membuat intersepsinya lebih besar dibandingkan vegetasi lain. Sistem perakaran tunggang dan daya rambah 2,25 meter (1,5 kali dari tinggi pohon). Selain itu, serasah yang terbentuk akibat adanya tegakan pinus mengakibatkan air limpasan lebih besar daripada kemampuan menyerap ke dalam tanah.pada bulan Oktober 2015, kebakaran hutan yag terjadi di Kabupaten Sinjai, salah satunya kebakaran yang terjadi di area perbatasan Kecamatan Sinjai Barat dengan Kecamatan Sinjai Tengah. Kebakaran terjadi di kawasan hutan pinus (hutan produksi) dengan total area kebakaran 1,6 ha. Salah satu penyebab kebakaran adalah punting rokok kemudian merembet ke pangkal batang pinus. Sisi lain pinus adalah mudahnya serasah pinus terbakar. Pinus pun dapat tumbuh dengan baik pada wilayah dengan curah hujan 2.309 mm/tahun, sedangkan pada wilayah dengan curah hujan dibawah 1.500 mm/tahun lebih baik tidak ditanami pinus. Menurut Stasiun Meteorologi No. 420 Bikeru, curah hujan Kabupaten Sinjai adalah 1.097 mm/tahun. Sehingga, diyakini penyebab longsor tahun 2006 salah satunya adalah karena adanya keberadaan hutan pinus (alih fungsi hutan) (Payo-Payo, 2015). 40 319 pohon pinus di Sinjai ini sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan keterangan lain dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, bahwa hutan lindung yang ditanami pohon pinus merupakan hutan lindung yang diproduksi (Irfan F, 2014). Untuk mencapai target pemasukan daerah, pemerintah daerah menargetkan volume getah per tahunnya. Hal ini direalisasikan dengan Perjanjian Kerjasama Sadapan Getah Pinus No.800/138/Disbunhutl2007 antara Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan PT. Rakindo Utama Makmur, untuk mencapai target untuk melakukan penyadapan getah pinus sebanyak 1.000 ton/tahun. Hal ini yang diduga menjadi faktor alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, terlebih-lebih volume target per tahunnya belum memenuhi, yaitu hanya 800 ton/tahun. Secara tekhnis, lahan di kabupaten Sinjai, khususnya di Dusun Bonto, tidak cocok untuk ditanami tanaman Pinus. Hal ini juga sudah diatur dalam kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan tahun 200942. Untuk tujuan pengelolaan lingkungan hidup, maka hutan lindung dengan lereng kemiringan 45 derajat, seharusnya di tanami dengan pohon atau kayu berjenis endemik, contohnya, kemiri, rotan, enau, damar, dan lainlain. Namun, kebijakan tahun 2009 ini tidak diindahkan oleh pihak pemerintah kabupaten Sinjai43. Padahal, seperti telah diketahui bahwa lereng kemiringan wilayah dusun Bonto ialah 45 derajat.Akibatnya tahun 2011, di Kabupaten Sinjai hampir 100% hutan lindung sudah dikonversi menjadi hutan produksi. Hal ini didukung oleh munculnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Perda yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai ini bertentangan dengan moratorium alih fungsi lahan hutan berdasarkan keputusan kementerian di tingkat pusat44 serta RTRW kebupaten Sinjai 2012-202345. Hutan, Hutan Pinus dan Perlawanan Rakyat untuk Penghidupan Tahun 1984, ditengah-tengah gencarnya penanaman pinus, terjadi penolakan yang dilakukan sejumlah warga Dusun Bonto. Warga pada saat itu berhasil menghentikan penanaman pinus di kawasan hutan di Dusun Bonto. Hal ini menunjukkan bahwa warga tidak diam ketika sebagian wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan, terlebih dalam proses penunjukan kawasan hutan yang ada disekitarnya tidak melibatkan warga. Penolakan warga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kawasan yang kini menjadi kawasan hutan negara merupakan sumber penghasilan warga, karena di dalam kawasan tersebut terdapat kebun-kebun warga. Kedua, di kawasan hutan merupakan tempat 42 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data Dinas Kehutanan tahun 2009, luas lahan hutan pinus di Kabupaten Sinjai mencapai 3.155 ha dengan jumlah pohon 1.009.200 pohon (Irfan F, 2014). 44 Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo surat Menhut No. 1712/MenhutVII/2001 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia. Departemen Kehutanan tidak lagi mengeluarkan ijin alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan budidaya pertanian/perkebunan (dalam (Irfan F, 2014)). 45 Perda No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sinjai 2012-2023, dalam Bab I Pasal 1 ayat 31 bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi berdasarkan ketentuan umum zonasi kawasan pada pasal 67 ayat 1 meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga hutan lindung. Pada Bab I pasal 1 ayat 32, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung pada pasal 31 ayat 3, luas keseluruhan sebesar 10.996 ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Tellulimpoe. Pada pasal 61 ayat 2, ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung kegiatan apa saja yang diperbolehkan, diantaranya adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan selebihnya kegiatan yang diperbolehkan adalah seluruh kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. Pada pasal 43 huruf b, mengenai kawasan peruntukan pariwisata alam, salah satunya terdiri dari hutan pinus. Namun, untuk peruntukkan kawasan hutan pinus tidak dijelaskan lebih lanjut tepatnya berada di kecamatan mana dan desa mana. 43 320 bersejarah bagi warga dusun Bonto, karena disanalah tempat asal nenek moyangnya yaitu wilayah Pattontongan dan Kampung Lappara’.Pattontongan dianggap sebagai wilayah asal muasal nenek moyang mereka sedangkan Kampung Lappara’ merupakan pemukiman pertama warga dusun Bonto sebelum dipindahkan secara paksa oleh tentara (usai penumpasan pemberontakan gerilyawan yang dipimpin Qahhar Mudzakkar) ke tempat tinggal sekarang di tepi-tepi lereng curam. Sebagian wilayah dusun Bonto, desa Kompang masuk ke dalam penunjukan kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Luasan wilayah yang ditunjuk menjadi kawasan hutan 460 Ha dari luas keseluruhan desa 1.457 Ha (Sirimorok, Batiran, & Sanusi, 2014). Dalam referensi lain, luas kawasan hutan lindung di desa Kompang adalah 600 Ha dan hutan produksi 500 Ha (Ngakan, Achmad, Wiliam, Lahae, & Tako, 2005; Wahid, Bohari, & Achmad, 2015). Berdasarkan Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai 2012-2023, Pasal 38 ayat 2 menyatakan bahwa “kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Sinjai terdapat di empat wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo, dengan luas total 7.193,20 Ha”. Berdasarkan penuturan Pak Ansar, kawasan hutan yang kini menjadi hutan negara, dulunya adalah hutan asli milik masyarakat. Warga senantiasa menggantungkan hidup dengan apa yang mereka tanam di hutan itu.46 Status hutan tersebut, hingga saat ini masih dalam proses penunjukan, belum kepada tahap penetapan apalagi pengukuhan kawasan hutan47. Gerakan penolakan warga dipimpin oleh tokoh agama salah satu tarekat di dusun Bonto, yaitu Puang Suyuti. Berdasarkan penuturannya, ia mengerahkan para pemuda dusun untuk melawan petugas dari Dinas Kehutanan yang sedang melakukan proses penanaman pinus di wilayah mereka. Dengan alasan kultural untuk mempertahankan Kampung Lappara’ dan Pattontongan, mereka berupaya untuk menghadang kehadiran hutan Pinus. Bahkan, hingga saat ini di Kampung Lappara masih banyak warga yang bermukim di sana (sekisar 27 rumah)48 (Tim Peneliti Payo-payo, 2015). Untuk itu mereka menolak penunjukkan kawasan hutan yang diterbitkan tahun 1982. Walaupun demikian, aksi ini hanya menghentikan proses penanaman pinus saja, tetapi tidak membatalkan kebijakan penunjukkan kawasan hutan di wilayah Dusun Bonto. Pengaturan kawasan hutan di Indonesia, khususnya sejak era pemerintahan Orde Baru, diatur secara terpusat. Di Sulawesi Selatan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur yang tertuang dalam Pasal 8 ayat(1)49 bahwa pemerintah kabupaten akan melaksanakan urusan kehutanan tetapi tugas koordinasi dan pengawasan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini diperkuat dengan peraturan yang dikeluarkan tahun 1998, yaitu PP No. 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah50. Berdasarkan peraturan tahun 1968 tersebut, tahun 1981 kebijakan penutupan kawasan hutan di desa Kompang mulai diterapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Dengan 46 Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015 Terdapat beberapa tahapan untuk menetapkan status kawasan hutan di Indonesia, dimulai dari tahap penunjukkan, penataan batas kawasan hutan, diikuti dengan tahapan penetapan dan diakhiri dengan pengukuhan. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.50/Menhut-11/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. 48 Wawancara dengan Puang Sayuti Hajarang pada 22 November 2015 49 Yang menyatakan bahwa: “Pemangkuan hutan, …dst, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, …dst, terkecuali untuk wilayah bekas NIT, dimana urusan kehutanan telah ada pada Daerah Swatantra Tingkat II”. 50 Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I adalah: (a) pengelolaan taman hutan raya, dan (b) penataan batas hutan. Adapun urusan di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah: (a) penghijauan dan konservasi tanah dan air, (b) persuteraan alam, (c) perlebahan, (d) pengelolaan hutan milik/hutan rakyat, (e) pengelolaan hutan lindung, (f) penyuluhan kehutanan, (g) pengelolaan hasil hutan non kayu, (h) perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal-areal buru,(i) perlindungan hutan, dan (j) pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan. 47 321 mulai membatasi akses warga untuk menanam dan mengambil hasil panen di wilayah yang termasuk kawasan hutan. Kegiatan warga di dalam hutan dikategorikan sebagai aktivitas merusak kawasan hutan, dan diancam dengan ancaman dipenjarakan. Setelah dikeluarkannya kebijakan penutupan kawasan hutan, setahun kemudian kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, dengan dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, yang didalamnya disebutkan bahwa ada sekitar 3,6 juta Ha lahan di Sulawesi Selatan yang ditunjuk menjadi kawasan hutan. Namun, hal ini tidak mengubah persepsi warga tentang keberadaan hutan tersebut, bahkan hingga sekarang, dimana dianggap sebagai hutan produksi yang hasilnya bisa dimanfaatkan warga untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Kebijakan tahun 1982 tersebut kemudian diperbaharui pada tahun 1999 dengan penjelasan tentang luasan wilayah hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Didalam SK Menteri Pertanian dan Kehutanan No 890/kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dinyatakan bahwa kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang luasnya 3.879.771 Ha (lebih luas dibandingkan kebijakan sebelumnya yang hanya 3,6 juta Ha). Rinciannya adalah untuk penunjukkan sebagai kawasan suaka alam51, kawasan pelestarian alam52, taman buru (darat dan perairan) seluas 789.066 Ha, untuk hutan lindung53 seluas 1.944.416 Ha, untuk hutan produksi54 terbatas seluas 855.730 Ha, untuk hutan produksi tetap seluas 188.486 ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 102.073 Ha (Dinas Kehutanan Sulsel, 2012). Penunjukkan kawasan-kawasan tersebut meliputi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh warga setempat termasuk warga Dusun Bonto di desa Kompang. Namun, pada kebijakan yang dikeluarkan tahun 200955, kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan berkurang menjadi hanya 2,7 juta Ha56, atau berkurang sekitar 1 juta Ha. Apakah hal ini merupakan respon dari penolakan warga yang terjadi pada tahun 1984 atau bukan, akan dapat dilihat langsung kenyataannya di lokasi, yaitu di Dusun Bonto, apakah mereka kemudian bisa mengakses wilayah kebunnya yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan atau tetap dilarang. Dengan adanya kebijakan ini, tanah yang mulanya dikuasai oleh warga desa Kompang, baik tanah yang bersertifikat maupun tidak menjadi bagian dari kawasan hutan negara. Sehingga, pada masa awal kebijakan ini diberlakukan, kebun-kebun warga yang sudah ditanami kopi, cengkeh dan kakao tidak bisa diakses termasuk tidak bisa diambil hasilnya. Tetapi warga tidak tinggal diam, beberapa warga nekat untuk mengambil haknya dengan melintasi batas kawasan hutan tersebut untuk mengambil hasil kebunnya. Tindakan 51 Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian dalam peraturan pemerintah ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik daratan ataupun perairan dengan fungsi pokoknya sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman ekosistemnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat di areal kawasan tersebut. Selain itu, penetapan kawasan suaka alam terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa. 52 Sedangkan kawasan pelestarian alam terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam. 53 UU No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 1 (huruf h) hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah .Sedangkan, berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian kawasan hutan lindung.Ini pun diterapkan di hutan dusun Bonto.Lagi-lagi warga tidak bisa mengakses kawasan hutan. 54 Dan ayat 2, hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. 55 SK Menteri Kehutanan RI No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 56 Dengan rincian kawasan suka alam/kawasan pelestarian alam (851.267 Ha), hutan lindung (1.232.683 Ha), hutan produksi terbatas (494.846 Ha), hutan produksi tetap (124.024 Ha) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (22.976 Ha). 322 ini berakibat pada proses hukum yang harus dihadapi warga, bahkan beberapa warga dipenjara (Sirimorok, Batiran, & Sanusi, 2014, p. 12). Atas kejadian tersebut, warga melakukan advokasi dengan melakukan negosiasi, yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dengan Dinas Kehutanan setempat untuk mengijinkan warga mengambil hasil atas tanaman yang sebelumnya mereka tanam di kebunnya.57 Walaupun demikian, kebijakan penunjukan hutan dan penutupan lahan ini tetap membuat warga tidak bisa kembali ke tempat tinggal asal mereka. Kebijakan kehutanan tahun 1980-an dan diikuti tahun 1999 merupakan rantaian kesulitan warga mengakses hutan yang sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Kebijakan penghijauan dan reboisasi hutan tahun 1976 juga menjadi tonggak dimana warga mulai sulit mengakses kawasan hutan. Inpres Nomor 8 tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang merupakan bantuan langsung dari pemerintah yang dananya berasal dari APBN (tahun anggaran 1976/1977). Kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, termasuk pengadaan bibit dan penanamannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melakukan penanaman kembali atau meremajakan pohon-pohon serta jenis tanaman lain di hutan negara dan di areal lain berdasarkan rencana tata guna tanah untuk hutan58 yang dilaksanakan diatas lahan seluas kurang lebih 312.500 Ha59. Program reboisasi ini diperkuat lagi pada tahun 1980 dan 1993, khususnya tentang bagaimana mengatur pendanaan untuk merealisasikan program ini. Dalam Keppres No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Reboisasi, terdapat ketentuan tentang keharusan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) skala besar untuk membiayai kegiatan rehabilitasi lahan hutan dan regenerasi areal konsesi pasca tebangan. Dengan ketentuan ini, setiap perusahaan pemegang konsesi wajib menyerahkan dana jaminan reboisasi60 yang ditujukan untuk menjaga dan terus menambah kualitas serta kuantitas pohon di hutan. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan sebagaimana tujuan dari diadakannya peraturan ini, seringkali terdengar bahwa terdapat penyalahgunaan dana reboisasi yang terkumpul (Down to Earth, 2002, pp. 18,19 dan 29)61. Untuk itu, pada tahun 1993, berdasarkan Keppres No. 40/1993, pengaturannya lebih diperketat, dimana tarif dana reboisasi ditentukan secara terpusat dan berbeda di setiap wilayah di kawasan Indonesia62. 57 Wawancara dengan Kepala Desa Kompang Ansar, pada 29 September 2015 Pasal 2 Inpres No. 8/1976 59 Pasal 4 Inpres No. 8/1976 merinci kegiatan-kegiatan penanaman diatas lahan seluas 300.000 Ha, reboisasi seluas 100.000 Ha dan untuk proses pengadaan bibit diatas lahan seluas 2.500 Ha. 60 Besar dana jaminan reboisasi dan permudaan iuran areal HPH: US.$.4 (empat dollar Amerika) untuk setiap meter kubik kayu semua jenis yang diproduksi dan US.$.0,50 (lima puluh sen dolar Amerika) untuk setiap meter kubik chipwood yang diproduksi. Dana jaminan ini digunakan untuk meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas tegakan hutan pasca tebangan di dalam areal HPH. (Pasal 3 Keppres No. 35/1980) 61 Dana reboisasi diserobot oleh perusahaan-perusahaan beserta koleganya. Seperti PT. Inhutani yang menguasai hutan dalam jumlah besar di luar Jawa (Sulawesi Selatan). Dana ini digunakan untuk pengrusakan hutan (penyediaan dana pembuatan kayu insdustri) 62 Pasal 1 (1) Keppres No. 40/1993, yaitu “Mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 sebagai berikut: (1) Mengubah Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) besarnya dana reboisasi ditetapkan dengan tariff sebagai berikut: (a) untuk wilayah Kalimantan dan Maluku: (1) US$. 16 (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis meranti, (2) US$13 (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran. (b) untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi: (1) US$. 14.- (empat belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. (2) US$. 12.- (dua belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran. (c) untuk Wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara: (1) US$. 13.- (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. (2) US$. 10.50 (sepuluh dollar lima puluh sen dollar Amerika) setiap meter kubik kelompokjenis Rimba Campuran. (d) untuk seluruh Wilayah Indonesia: (1) US$. 20.- (dua puluh dollar Amerika) setiap ton kelompok jenis Ebony. (2) US$. 16.- (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik jenis Jati Alam. (3) US$. 18.- (delapan belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana. (4) US$. 2.- (dua dollar Amerika) setiap meter kubik bahan baku serpih/partikel, limbahpembalakan dan sortimen khusus lainnya.(2)Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan-baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya diatur oleh Menteri Kehutanan. "Ayat 2 “Mengubah Pasal 10, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: pasal 10: (1) Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajibdilunasi oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut: (a) Disetor langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada Bank yang telah ditetapkan, atau; 58 323 5. KESIMPULAN Proses penunjukkan kawasan hutan melalui kebijakan kehutanan di Indonesia merupakan salah satu alat proses perebutan sumber-sumber penghidupan rakyat. Salah satunya di Dusun Bonto, Desa Kompang, Kabupaten Sinjai.Sejak ditetapkannya sebagai kawasan dusun ini pada tahun 1982 (SK Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan), sebagian Dusun Bonto berubah menjadi kawasan hutan lindung (seluas 460 Ha dari luas 1.457 Ha). Secara legal formal, dengan proses penunjukkan kawasan hutan ini, maka warga di sekitarnya tidak bisa mengakses wilayah tersebut, padahal sebelumnya warga sudah menguasai lahan di kawasan tersebut dan mengelolanya untuk menjadi sumber mata pencaharian dengan potensi sumberdaya alam yang sangat kaya. Sejak saat itu, kawasan tersebut ditanami dengan pohon pinus, yaitu Pinus Merkusii Jung et de Vriese. Sejumlah ahli telah mengkaji bahwa tanaman pinus adalah tanaman yang dapat merusak kondisi tanah, khususnya apabila di sekitarnya terdapat lahan pertanian dan dekat dengan areal perkampungan.Warga Dusun Bonto dari waktu ke waktu senantiasa menjaga hutan yang berada di sekitar pemukiman mereka. Cara yang mereka pilih adalah dengan menanamnya dengan apa yang bisa menghasilkan dan bisa menghidupi kehidupan mereka. Dengan tanpa merusak hutan yang dari dulu telah ada. Karena bagi mereka menjaga warisan dan tanah nenek moyang merupakan hal yang sangat penting. Salah satu tanaman yang kemudian menjadi sumber penghidupan warga adalah cengkeh. Pada masa penunjukkan kawasan hutan serta penanaman pinus, maka cengkeh merupakan tanaman yang diperjuangkan oleh warga Dusun Bonto. Cengkeh telah ditanam sejak 1971-1980, hingga sekarang hasil panen cengkeh terhitung sangat banyak. Hampir setiap petani di dusun Bonto memiliki pohon cengkeh, baik itu yang ditanam di pekarangan rumah ataupun di kebun-kebun di sekitar gunung Pattontongan (termasuk di kawasan hutan pinus). Selain itu, adanya cengkeh dijadikan oleh warga sebagai strategi warga untuk tetap bertahan hidup. Meskipun sumber air yang biasa dijadikan oleh warga untuk menyiram cengkeh di musim kemarau mulai berkurang dan menghilang. Dan salah satu penyebab yang diyakini oleh warga terkait hilangnya sumber air warga Dusun Bonto adalah karena keberadaan pinus.Warga tetap bertahan ditengah-tengah berkurangnya daya lingkungan yang menjadi penyokong bagi sumber penghidupan mereka. Meskipun, beberapa petani cengkeh mengeluhkan bahwa pohon cengkehnya tahun ini banyak yang mati, kering dan hasil panennya berkurang, namun tanaman ini tetap menjadi sumber penghasilan utama warga hingga saat ini. Cengkeh pun menjadi komoditas utama pertanian warga di Dusun Bonto. Begitu eratnya relasi antara warga Dusun Bonto dengan lingkungan di sekitarnya. Dapat dilihat dari pemaparan di atas. Kebijakan penanaman pinus pun dapat dihentikan oleh warga (meskipun tidak semua kawasan hutan yang telah ditanami pinus), namun setidaknya warga pun dapat menuai hasil dari perlawanan yang mereka lakukan. Peran salah satu lembaga in-formal yang berada di Dusun Bonto dapat menjadi pegangan bagi warga untuk menjaga kelestarian hutan dan tanah nenek moyang. Pemimpin Tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Bonto memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi (b) Bagi Wajib Pungut dan Wajib Setor yang melakukan ekspor kayu olahan dipotong langsung melalui Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pemberitahuan eksporbarang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C). (2) Wajib Pungut dan Wajib Setor yang dapat melakukan pelunasan Dana Reboisasi dengan carasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (3) Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b wajibdisetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (4) atas keterlambatan penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dana Reboisasi yang terlambat disetor. (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib diperhitungkan dan disetorkan langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada saat penyetoran atau pada saat pemotongan langsung pada saat negosiasi wesel atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)”. 324 warga, melebihi pengaruhnya aturan pemerintah lokal. Segala yang didawuhkan oleh pemimpin tersebut setidaknya tidak bisa dibantah oleh warga lainnya. Namun, ini bisa dijadikan senjata oleh warga Dusun Bonto sebagai upaya perlawanan warga dengan segala aturan pemerintah yang dapat mengambil sumber penghidupan mereka. 6.DAFTAR PUSTAKA Contreras, A., Hermosilla, & Fay, C. (2006). Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan. Bogor: World Agroforestry Centre. Dinas Kehutanan Sulsel. (2012). Profil Kehutanan Sulawesi Selatan. Retrieved Desember 17, 2015, from Prov Sulawesi Selatan: http://sulselprov.go.id/potensi/kehutanan/2012/_PROFIL%20KEHUTANAN%20 Sul-Sel.pdf Down to Earth. (2002). Forest People and Rights. Down o Earth Special Report. EA, P., & dkk. (2013). Ekspedisi Cengkeh. Makassar: Ininnawa dan Layar Nusa. Irfan F, M. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi. Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin. Kompang, R. D. (2015). Li, T. M. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Tangerang Selatan: Margin Kiri. Moellono, I., & Djohani, R. (1996). Berbuat Bersama Berperan Serta: Acuan Penerapan Particfipatory Rural Appraisal. Bandung: Driya Media. Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi yang Mandiri. Bogor: CIFOR. Payo-Payo, P. P. (2015). Pinus di Desa Kompang. Belum dipublikasikan. Safitri, M. A. (2000). Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi Kebijakan dan Praktik. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Salim, I., & Ni'am, L. (2012). Merancang Bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten (Maluku Tenggara, Sinjai, Ende, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah). Yogyakarta: Insistpress. Santoso, H. (2004). Perlawanan di Simpang Jalan; Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa. Jogjakarta: DAMAR. Sirimorok, N., Batiran, K., & Sanusi, R. (2014). Bermukim di Lereng Maut: Bagaimana Bencana Tercipta di Dua Desa Sulawesi Selatan. Transformasi Sosial, 16. Soemarwoto, O. (1997). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Suciati, A., Anggoro, A. D., Ristanto, D., & dkk. (2007). Hutan dan Manusia; Mendorong Pengelolaan Hutan oleh Rakyat. Jogjakarta: KARSA bekerjasama dengan SGP PTF UNDP-EC-SEAMEO SEARCA. Tim Konphalindo. (2001). Bisnis Kehidupan; Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi dan Keserakahan Manusia. Judul Asli: The Life Industry: Biodiversity, People and Profit. Yogyakarta: Read Book. Tim Peneliti Payo-payo. (2015). Pinus di Desa Kompang. Makasar: Belum dipublikasikan. Wahid, A. Y., Bohari, N., & Achmad. (2015, April). Penegakkan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan: Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Hasanuddin Law Review, 1(1). 325 Daftar Informan No. 1. 2 Nama Sultan Alwy Sayuti Hajarang 3 4 Asikin Dg. Pella Ansar 5 6 7 Ibu Suryani Anwar Unding 8 9 10 Bakrin Tajuddin Pak Hasyir Keterangan Informan Kepala Dusun Bonto Puang Dusun Bonto dan merupakan pemimpin dari tarekat Khalwatiyah Samman di Dusun Bonto Kepala Dusun Barugae Kepala Desa Kompang Salah seorang warga di Dusun Bonto Salah seorang warga di Dusun Bonto Ketua RK 07 Kampung Lappara’ Dusun Bonto Salah seorang warga di Dusun Bonto Salah seorang warga di Dusun Bonto Salah seorang warga di Dusun Bonto Tanggal Wawancara 15 Oktober 2015 8 Oktober 2015 dan 22 November 2015 29 September 2015 dan 3 Oktober 2015 6 Oktober 2015 9 Oktober 2016 20 Oktober 2015 14 Oktober 2015 22 Oktober 2015 16 November 2015 326 HETEROTOPIA PERANG KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT MADURA:STUDI GERAKAN SOSIAL MAKNA TANASANGKOL Iskandar Dzulkarnain¹) JurusanSosiologi, FISIB, Univ. Trunojoyo Madura Email: [email protected] Abstrak Tanasangko lbagi masyarakat Madura merupakan warisan yang harus dijaga, karena memiliki makna sakralitas yakni sebagai ruang yang mempertautkan kehidupan saat ini dengan paraleluhur. Karenanya, tanasang kolan tidak boleh dijual tanpa ada alasan, karena akan mengakibatkan ‘laknat’ dari paraleluhurnya. Neoliberalisme dan gaya hidup masyarakatlah penyebab hilangnya nilai sacral itas tersebut. Industrialisasi, penambangan, tambak, dan perumahan merupakan berbagai bentuk pengambil alihan atau ‘perampasan’ tersebut, baik individu, maupun perusahaanperusahaan. Penelitian ini ingin memahami gerakan social dan pergeseran makna mengenai sacral itas tanasangkol. Sedangkan teorinya menggunakan teori Michel Foucault tentang ruang heterotopia. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan wawancara danobservasi partisipan. Hasil penelitiannya adalah muncullah gerakan social kelompok keagamaan Madura yang diketuai oleh Seketaris PCNU Kabupaten Sumenep Madura, yang dikemas dalam bentuk kompolantera’bulan. Sebuah perkumpulan keagamaan yang melakukan ragam kegiatan advokasi, pemberdayaan, pembelajaran, dan kerja social untuk mengembalikan daulat warga Madura dalam membentuk ruang heterootopia di Madura melalui kepemilikan kembali tanasangkolan. Kata Kunci: Tanasangkol, Heterotopia, Neoliberalisme, dan Madura Abstract Tanasangkol for the people of Madura is a legacy that must be preserved , because it has a sacred meaning that as a space that connects the current life with the patriarchs. Therefore ,tanasangkolan not be sold without any reason , because it would result in ' anathema ' of the ancestors. Neoliberalism and lifestyle of the communities in the cause of the loss of the sacred values. Industrialization, mining, ponds , and housing are various forms of expropriation or 'deprivation' is, individuals, and corporations. This study wanted to understand the social movement and the shift in the meaning of the sacred tanasangkol. While his theory using the theory of Michel Foucault's heterotopia space. While the method of research used qualitative method with interviews and participant observation. His research is a social movement arose Madura religious group, chaired by the Secretary PCNU Sumenep Madura, which is packaged in the form kompolantera’bulan. A bevy of diverse religious conduct advocacy, empowerment, learning, and social work to restore the good fortune of citizens in shaping space heterootopia Madura through repossession tanasangkolan. Keywords: Tanasangkol, Heterotopia, Neoliberalism, And Madura 1. PENDAHULUAN Tulisan hasil penelitian ini dibuat di Desa Masalima Pulau Masalembu, sebuah kepulauan yang hidup dengan berbagai kearifan lokal nelayannya dan hidup damai dengan tiga etnis mayoritas, yakni etnis Mandar, Bugis, dan Madura.Potensi perikanan yang luar biasa dan hidup kesederhanaan masyarakatnya serta kesadarannya telah melahirkan pola penangkapan perikanan yang tetap menggunakan pola tradisional, sehingga potensi perikanannya tetap terjaga dengan baik bahkan berlimpah.Namun, banyak nelayan luar yang memanfaatkan ini dengan cara yang salah yakni menggunakan illegal fishing (yang dilarang oleh pemerintah), sehingga nelayan menangkap mereka.Ragam negoisasi 327 mengalami kegagalan dan akhirnya dibuatlah kesepakatan untuk mengganti rugi, yang terjadi akhirnya malah masyarakat Masalembu dianggap ‘perompak’ dan ditahan oleh Pemerintah. Di sinilah seharusnya peran Pemerintah untuk menjaga masyarakatnya diperlukan bukannya malah alpha di saat masyarakat membutuhkannya.Atau malah pemuda yang mampu menjaga keutuhan kearifan masyarakat Madura bukan malah menjadi actor yang mencari keuntungan dari kebodohan masyarakat. Karena Pemerintah dan Pemudalah yang akan mencetak sebuah peradaban di sebuah daerah termasuk di Madura. Hal itulah potret yang sama terjadi di Kecamatan Dungkek dan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, di mana masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan tanahsangkolnya dari jarahan para pemilik modal baik local, nasional, maupun internasional. Identitas dan nilai-nilai kearifan budaya untuk menjaga tanahsangkol telah bergeser untuk menjual dan merubahnya menjadi identitas-identitas nilai ekonomis kapitalis, seperti dibelikan mobil, rumah perumahan di wilayah perkotaan, dan untuk berbelanja di Surabaya maupun kota besar lainnya. Pergeseran nilai-nilai tersebut yang kemudian menyebabkan terserabutnya nilainilai peradaban ke-Madura-an, yang tersisa hanyalah nilai globalisasi, modernitas, dan kapitalisasi. Gaya hidup dan ragam upaya untuk menjadi klas social atas melalui imitasi identitas kepemilikan rumah, mobil, dan aksesoris lainnya merupakan factor pendorong penjualan secara ‘suka rela’ ke pihak luar. Perubahan kepemilikan tanah dari ‘Pak Abdullah’ ke ‘Pak Kapitalis’ lambat laun akan menyebabkan keresahan yang luar biasa bagi masyarakat local Madura. Potret itu sudah mulai terlihat ketika hampir semua wilayah pesisir utara Madura Timur (Kecamatan Dungkek dan Batang-Batang) sudah berubah menjadi tambak-tambak.Kegelisahan dan upaya untuk melakukan gerakan social penyadaran masyarakat sudah menimbulkan ragam konflik, meskipun belum sampai mengakibatkan korban jiwa. Melalui kompolan tera’ bulan inilah para pemuda yang diketuai oleh Seketaris PCNU Kabupaten Sumenep yakni K. Dardiri Zubairi, melakukan ragam advokasi, pendidikan, dan lain sebagainya untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga tanahsangkolannya demi para anak cucu mereka kelak. Hal inilah yang menjadi landasan utama kajian ini, yakni gerakan social kompolan tera’ bulan dalam gerakan menjaga tanah sangkol bagi masyarakat Madura. 2. TINJAUAN PUSTAKA Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori heteroutopianya Michel Foucault dari bukunya ‘The Order Of Things (1989)’.Heterotopia merupakan Penaklukan Ruang Publik.Secara sosiologis konsep ini merupakan gabungan dari 'hetero+utopia' yakni ruang yang tidak mengenal adanya klas social maupun pembedaan cultural, atau juga latar belakang individu masyarakat.Di mana ruang yang diinginkannya adalah ruang yang ideal, seperti utopia, yakni ruang publik yang bebas kompetisi material (capital/ekonomi dan politik) dan konflik. Namun, realitas ruang saat ini telah berubah menjadi 'ruang ideal' dan 'ruang nyata', sebagai konsekuensi atas ragam okupasi kapitalisme yang akan selalu melahirkan berbagai bentuk kepentingan.Lebih lanjut, Foucault menyebut konsep "heterotopia" untuk menunjukkan pentingnya ruang yang non hegemonic.Meskipun realitas saat ini malah menunjukkan bahwa ruang (space) itu cenderung hierarchytopia. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam studi ini, penelitian kualitatif akan dioperasikan melalui analisis deskriptif, dengan melakukan reinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti (Vredenberg, 1986: 34). Jadi pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tapi 328 mencakup analisis dan interpretasi tentang data itu (Singarimbun & Effendi (ed), 1989: 45). Sedangkan secara metodologis dasar penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni refleksifitas (réflexivité), yang merupakan istilah dari fenomenologi.Dalam refleksifitas terdapat dua unsur penting, yakni unsur yang mengacu pada interaksi dan yang mengacu pada konteks institusional yang dibangun.Refleksifitas tidak dicampuraduk dengan refleksi. Ketika kita mengatakan bahwa orang memiliki praktik refleksif, hal ini tidak berarti ia memikirkan apa yang dilakukan atau yang sedang dilakukan. Para anggota sudah tentu tidak memiliki kesadaran reflektif atas tindakannya. Karena ia tidak mampu, jika mereka sadar, mereka akan mengikuti tindakan-tindakan praktik yang bisa melibatkan mereka. Seperti yang ditekankan oleh Garfinkel, para anggota tidak memiliki perhatian terhadap keadaan praktik sekitarnya dan tindakan praktiknya. Mereka tidak akan berusaha untuk menteorisasikan dan menganggap refleksifitas tersebut sebagai sesuatu yang seharusnya, karena mereka sudah mempunyai apa yang disebut sebagai ‘stock of knowledge’, tetapi mereka harus bisa mengenali, membuktikan, dan bisa mengamati setiap anggota lainnya melalui sifat rasional di dalam praktik mereka yang konkret (Denzin & Lincoln, 1994: 262-264). Studi ini menggunakan data kualitatif (Nawawi, 1995) dan data kuantitatif (Koentjaraningrat (ed), 1997: 31), kedua data ini digali dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui observasi partisipan (Moesa, 1999: 15) dan melalui wawancara mendalam terhadap unsur elemen masyarakat Sumenep yang diperkirakan mendukung untuk mendapatkan data dalam penelitian yang dikaji, dengan menggunakan interview guide atau dengan bahasa lain wawancara ini dilakukan berselangseling dengan observasi partisipan, dan secara berulang-ulang kepada informan yang sama. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN Saat ini, Madura yang sudah memiliki Jembatan Suramadu yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono diharapkan mampu memeratakan pembangunan antara Surabaya dan Madura, yang selama ini terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara industrialisasi di Surabaya dan di Madura.Industrialisasi merupakan salah satu dampak nyata dari direalisasikannya Jembatan Suramadu, yang diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat Madura melalui pembangunan-pembangunan yang diproyeksikannya.Sehingga seiring perkembangan jembatan Suramadu diharapkan memiliki ciri “Indonesianis, Maduranis, dan Islamis”. Namun, seringkali tidak diimbangi dengan penguatan kompetensi masyarakat Madura untuk bersaing dengan pihak luar dalam memanfaatkan proses industrialisasi di Madura. Masyarakat Madura yang mayoritas petani dan nelayan lambat laun ‘dipaksa’ untuk menjual tanah-tanah mereka dengan dalih industrialisasi, sehingga pada akhirnya mereka akan kehilangan lahan yang menjadi milik mereka sejak lama karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari nenek moyangnya (tanasangkolan). Keengganan menjadi petani bagi generasi muda dan gaya hidup konsumeris merupakan dampak yang paling nyata dari realisasi Jembatan Suramadu saat ini. Berbelanja dan menghabiskan banyak uang dari hasil penjualan tanasangkol ke Surabaya merupakan potret riil masyarakat Madura saat ini. Hal ini yang menjadikan banyak pemuda-pemuda Madura terutama pemuda Nahdliyyin membentuk kelompok kompolan tera’ bulan untuk memberikan penyadaran, pendidikan, advokasi, dan lain sebagainya bagi masyarakat Madura akan pentingnya menjaga tanasangkol. Berawal dari kemirisan inilah kelompok kompolan ini dibentuk,ketika banyak tanah-tanah di Kabupaten Sumenep yang telah dialih fungsikan dan dijual pada investor, baik lokal Madura, luar Madura, maupun Asing. Hampir semua daerah pesisir utara paling Timur Madura telah dialihfungsikan dan berpindah kepemilikan, mulai 329 dari Kecamatan Batu Putih, Batang-Batang, dan Dungkek.Pengalihfungsian dan penjualan tanasangkol katanya mau dibuat tambak udang oleh para investor.Pembuatan tambak udang tersebut saat ini tengah digarap.Ketika tanasakol sudah dialihfungsikan dan dijual kepada investor, baru banyak masyarakatMadura tercengang dan kebingungan, karena dalam kesehariannyamereka disuguhkan tontonan alat-alat berat, mobil kontainer, dan mulai berdatangannya orang-orang yang tidak dikenal bahkan cenderung asing bagi mereka.Selain itu, juga banyaknya tambak-tambak udang yang dijaga oleh anjing dan dibiarkan berkeliaran secara bebas. Padahal bagi masyarakat Madura anjing merupakan hewan yang paling dihindari dan menakutkan karena akan membawa najis bagi masyarakat Madura yang mayoritas muslim. Potret pengalihfungsian dan penjualan tanah sangat terlihat di beberapa wilayah di tiga kecamatan yakni Kecamatan Batu Putih, Batang-Batang, dan Dungkek, yakni di Desa Lapa Laok dan Lapa Daja, terutama pesisir pantai utara Madura timur. Saat ini pengalihfungsian dan penjualan tanasangkol tersebut terus melebar ke berbagai desa-desa lainnya, yakni DesaBungin-Bungin Kecamatan Dungkek, yakni wilayah makam Syekh Mahfudz, atau lebih dikenal Asta GurangGaring, keturunan Sunan Kudus. Kemudian, wilayah di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang hingga Pantai Badur Kecamatan Batu Putih, yang termasuk kawasan pariwisata. Pengalihfungsian dan penjualan tanasangkol telah menyebabkan ragam kecurigaan dari masyarakat Madura terutama pemuda-pemuda yang tergabung dalam kompolan tera’ bulan.Kecurigaan, ketakutan, dan kewaspaan pemuda-pemuda tersebut semakin kuat ketika di Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek ada lapangan Heli yang baru dibangun awal tahun 2015.Menurut aparat desa, lapangan Heli itu milik petinggi militer di Jakarta. Ada sesuatu yang disembunyikan, apa? Fakta di atas semakin menunjukkan bahwa makin banyak masyarakat Madura yang mulai meninggalkan sawahnya, ladangnya, dan tegalnya.Masyarakat Madura lebih ingin bekerja di bidang lainnya, yakni menjadi migrant ke Jakarta (sebagai penjaga toko) dan Kalimantan (sebagai pengemis).Padahal secara kebudayaan, masyarakat Madura memiliki nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan mengenaitanasangkolan (tanah warisan).Bagi masyarakat Madura tanasangkolan bukan hanya sekedar warisan benda yang akan menjadi capital belaka sebagaimana emas,karena bagi masyarakat Madura, tanasangkolanmemiliki makna sakralitas dan penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan. Tanasangkolan bagi masyarakat Madura memiliki makna sebagai ruang (space) yang saling mempertautkan kehidupan saat ini dengan para leluhurnya. Oleh karenanya, ketikatanasangkolandialihfungsikan bahkan dijual tanpa adanya alasan yang jelas bahkan terkesan untuk menguatkan nafsu birahi gaya hidupnya akan mengakibatkan‘laknat’ dari sudut nilai-nilai kearifan kebudayaan Madura. Kalau pun tanah tersebut dijual, biasanya akan dijual pada keluarga terdekatnya. Suatu saat jika mampu, tanah itu akan dibeli kembali oleh pemiliknya.Sebuah realitas masa lampau yang kini sudah terserabut akar sakralitasnya.Saat ini tanah sudah dilucuti sakralitasnya, tanasangkolan kini sepenuhnya dianggap benda yang bisa dipertukarmilikkan. Perubahan alam pikir dan gaya hidupmasyarakat Madura sejak terealisasinya Jembatan Suramadu dioperasikan merupakan potret riil masyarakat Madura saat ini. Termasuk persepsi dan keyakinan mereka terhadap nilai-nilai kearifan lokal mengenai sakralitas tanasangkol juga berubah. Di sinilah lagi-lagi kealphaan pemerintah dalam menjaga identitas dan keharmonisan masyarakat Madura, terutama melalui nilai-nilai sakralitas kearifan lokal mengenai kepemilikan tanasangkol.Karena bagi para pemuda yang tergabung dalan kompolan tera’ bulan persoalan mengenai tanasangkol ini sepertinya tidak mungkin lagi menunggu upaya penyelesaian dariPemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.Bagi mereka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep hanya menjadi penadah dari ragam kebijakan 330 Pemerintah Pusat dan Pemerinatahn Provinsi termasuk jugapara investor.Oleh karenanya menurut mereka saat inilah rakyatlah yang harus berjuang sendiri untuk menjaga tanahnya melalui kembali ke nilai-nilai kearifaan lokal sakralitas tanasangkolan. Para pemuda yang tergabung dalam kompolan tera’ bulan ini kemudian menguatkan nilai-nilai kearifan lokal sakralitas tanasangkol melalui jargon ideologisasi‘ajagatana, ajaganakpoto’ (menjaga tanah, menjaga anak cucu) yang mulai digelorakannya, jika masyarakat Madura tidak mau menjadi kuli atau penonton industrialisasi dari pembangunan didaerahnya sendiri.Lebih jauh lagi, ragam fenomena seperti ini biasanya akan melahirkan konflik.Melalui pemahaman inilah maka kemudian para pemuda kompolan tera’ bulanmembentuk gerakan social melalui ‘Barisan Ajaga Tanah Ajaga Na’potoh (Batan)’. Ragam upaya yang dilakukan oleh Batan, baik melalui advokasi, sosialisasi, pendidikan, maupun proses penyadaran bagi masyarakat Madura ternyata belum menghasilkan upaya yang optimal. Sehingga pada akhirnya mereka meminta waktu untuk audiensi dengan Bupati Kabupaten Sumenep dan terealisasi pada hari selasa tanggal 05 April 2016. Dalam audiensi tersebut pihak Barisan Ajaga Tanah Ajaga Na’potoh (Batan) dengan Bupati pada akhirnya menghasilkan empat kesepakatan, yakni: 1). Pemerintah Daerah akan memasang ‘plang’ atau papan larangan melakukan aktivitas tanpa mengantongi ijin, seperti di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, Desa Romben Barat Kecamatan Dungkek, Desa Lapa Daja Kecamatan Dungkek, dan desa-desa lainnya, 2). Pemerintah Daerah akan melakukan kajian hukum untuk melakukan moratorium terhadap tambak dan kegiatan investasi lainnya yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, 3). Pemerintah Daerah akan melindungi lahan pertanian dan perkebunan produktif, kawasan hijau dan kawasan lindung, dan sebagainya dalam Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Tata Wilayah yang saat ini akan dibahas, dan 4). Pemerintah Daerah bersama Organisasi Masyarakat akan melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya mempertahankan tanah. Dari empat keputusan bersama hasil audiensi antara Batan dan Bupati tersebut, para pemuda yang tergabung dalam Batan meminta instansi atau dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumenep untuk menjalankan kesepatan yang dibuat antara Bupati Dr. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si bersama Batan dalam menyikapi semakin maraknya pengalihfungsianatau penjualantanah menjadi tambak oleh investor secara sungguh-sungguh. Menurut para pemuda Batan empat kesepakatan tersebut sangat produktif dan sangat bagus, tinggal bagaimana Dinas-dinasterkait untuk menindaklanjutinya. Apalagi, di saat empat kesepakatan tersebut dibuat dan disepakati, Bupati langsung memerintahkan kepada para Pimpinan Dinas-dinasterkait yang hadir, yakni Dinas Bagian Hukum, Badan Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menindaklanjuti empat kesepakatan tersebut dengan cepat dan tepat. Para pemuda Batan berharap para Pimpinan Dinas-dinas terkait tersebut tidak hanya sekedar ikut audiensi, namun seharusnya dapat mengambil peran sesuai tupoksinya untuk segera menindaklanjuti empat kesepakatan tersebut. Para pemuda Batan ingin segera dapat memastikan empat kesepakatan hasil audiensi tersebut bias dapat segera dijalankan secara maksimal. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam rangka upayanya untuk menyelematkan tanasangkol, apalagi banyak tanasangkol tersebut pengalihfungsiannya dari lahan yang produktif oleh para investor seperti di Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, dan kecamatan lainnya, yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat Madura, meskipun tanah yang dimanfaatkan tersebut pada umumnya sudah dibeli oleh para investor (RRI. Co.Id/6 April 2016). 331 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memasang papan larangan ternyata tidak berjalan efektif.Pasalnya, operasi pengalihfungsian dan penjualan tanah ke lahan tambak udang masih tetap berjalan sampai detik ini.Bahkan pimpinan kompolan tera’ bulan seringkali mendapatkan ancaman fisik melalui SMS maupun telpon, baik dirinya maupun keluarganya.Realitas ini sangat kuat apalagi pembelian dan pengalihfungsian tersebut dimakelari oleh para tokoh informal Madura, yakni para Kiai dan Blater. Menurut Kuntowijoyo (1994: 87) kiai di Madura seringkali dinggap sebagai ‘organizing principle’ yang akan berdampak terhadap terbentuknya sentiment kolektif bagi masyarakat, sehingga akan menjadi otorisasi kiai bagi masyarakat Madura. Penguatan ini semakin kuat dengan cerminan social masyarakat Madura yang terpotret dalam bappakbabbu’ – guru – rato (orangtua – guru/kiai – raja/pemerintah), sebuah potret ketaatan hirarkis bagi masyarakat Madura (Dzulkarnain, 2013).Sedangkan blater merupakan elit social pedesaan masyarakat Madura yang memiliki kepandaian dalam hal ilmu kanuragan dan menggunakan instrument kekerasan.Di sinilah terdapat relasi dualitas yang sangat unik menurut Rozaki (2004) yakni relasi untuk saling menopang kekuasaan antarkeduanya.Sehingga, tidak heran jika kekerasan yang dilakukan oleh blater seringkali mendapatkan legitimasi keagamaan dari kiai. Sebuah kajian yang perlu dilanjutkan untuk melihat gerakan social lanjutan dari para pemuda yang secara institusi merupakan potret keagamaan terbesar di Madura yakni pemuda NU yang mengalami gesekan dengan sebagian para seniornya yakni kiai yang menjadi ‘makelar’ penjulan tanasangkol masyarakat Madura, serta potensi konflik ke depannya. Di sinilah hilang ruang (space) tanpa klas social, latar belakang ragam budaya, maupun non hegemonic bagi masyarakat Madura. Di mana ruang tersebut telah bergeser menjadi ruang perebutan status dan klas social menjadi arena pertarungan para kapitalis untuk memperkuat nilai-nilai individualitas dan penguatan konsumerisme masyarakat melalui ragam hiperrealitas gaya hidup yang terbangun melalui modernitas dan pembangunan. Heteroutopia yang dicita-citakan oleh Michel Foucault hanya akan menjadi arena perdebatan teoritik yang tidak ada ujungnya ketika melihat potret realitas terserabutnya nilai-nilai kearifan local sakralitas tanasangkolan. 5. KESIMPULAN Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal di anatarnya: 1. Mulai hilangnya nilai-nilai kearifan sakralitas masyarakat Madura mengenai tanasangkol 2. Gaya hidup dan pembangunan merupakan salah satu hal terserabutnya nilai-nilai sakralitas tanasangkol 3. Gerakan social pemuda NU yang tergabung dalam kompolan tera’ bulanyang kemudian menjadi kelompok dengan namaBarisan Ajaga Tanah Ajaga Na’potoh (Batan) mencoba melakukan advokasi, pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya menjaga tanasangkol bagi masyarakat. 4. Menurut pemuda Batan pemerintah alpha dalam mengawal dan menjaga area lahannya, sehingga ke-alpha-an tersebut harus dirubah menjadi penggerakan dari pemerintah untuk mengawal dan menjaga lahan atau areanya untuk masyarakat bukan untuk para investor 5. Upaya Batan dan Pemerintah Kabupaten ini akhirnya menghasilkan empat kesepakatan hasil audiensi, yakni: a. Pemerintah Daerah akan memasang ‘plang’ atau papan larangan melakukan aktivitas tanpa mengantongi ijin, seperti di Desa Lombang 332 Kecamatan Batang-Batang, Desa Romben Barat Kecamatan Dungkek, Desa Lapa Daja Kecamatan Dungkek, dan desa-desa lainnya. b. Pemerintah Daerah akan melakukan kajian hukum untuk melakukan moratorium terhadap tambak dan kegiatan investasi lainnya yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. c. Pemerintah Daerah akan melindungi lahan pertanian dan perkebunan produktif, kawasan hijau dan kawasan lindung, dan sebagainya dalam Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Tata Wilayah yang saat ini akan dibahas. d. Pemerintah Daerah bersama Organisasi Masyarakat akan melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya mempertahankan tanah 6. Kiai dan blater telah menjadi ‘makelar’ dalam pengalihfungsian dan penjualan tanasangkol tersebut, yang menyebabkan sulitnya terealisasi empat kesepakatan tersebut, bahkkan coordinator Batan seringkali mendapatkan ancaman. 6. DAFTAR PUSTAKA Dzulkarnain. Iskandar. 2013. Dekonstruksi Sosial Budaya Alaq Dalaq di Madura, Pararaton: Jogjakarta Foucault. Michel. 1989. Orders of Things: An Archaeology Of The Human Sciences, London and New York: Rutledge Kuntowijoyo.1994. ‘Memahami Madura Sebuah Pendekatan Sosial Historis, Ekologi dan Kependudukan’, dalam Radikalisasi Petani, Bentang: Jogjakarta Moesa. Ali Maschan. 1999. Kiai Dan Politik, Wacana Civil Society, LEPKISS: Surabaya Nawawi.Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, cet. II, UGM Press: Yogyakarta Rozaki. Abd. 2004. Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar Di Madura, Pustaka Marwa: Jogjakarta Singarimbun, Masri. 1989. “Metode dan Proses Penelitian”, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed). Metode Penelitian Survei, LP3ES: Jakarta Vredenberg.Jacob. 1986. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Gramedia: Jakarta RRI. Co.Id/6 April 2016 333 RENEGOSIASI MASYARAKAT ADAT DI TENGAH ARUS PERGESERAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN HUTAN Dr. Caritas Woro Murdiati Runggandini, SH. MHum. Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta [email protected] Abstrak Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia mengalami gelombang perubahan yang lamban bila dikomparasikan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Lambannya perubahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya respon negara terhadap dinamika perubahan yang terjadi di aras lokalitas, khususnya masyarakat adat. Masyarakat adat yang tinggal dalam dan sekitar hutan sering dikategorikan sebagai orang miskin, tidak berpendidikan, malas, tradisional dan pelaku pembalakan liar. Tetapi di sisi lain, mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang kearifan lokal: lebih memiliki komitmen untuk perlindungan dari pada eksploitasi, mempunyai lembaga sosial untuk menyelesaikan konflik, memiliki komitmen mewujudkan keadilan sosial dan demokratisasi. Munculnya banditisme dan hilangnya kemampuan diri untuk mengelola hutan adalah situasi yang mendesak untuk melakukan dekonsttruksi terhadap paradigma pengelolaan hutan oleh negara. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian normatif ini, yang diteliti adalah data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Terhadap data yang diperoleh melalui penelitian normatif, digunakan alat bantu untuk mempertajam pembahasan dengan mempergunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Dekonstruksi dilakukan melaui format ”renegosiasi” pengelolaan hutan yang lebih adil, bermartabat dan mengutamakan persamaan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 1) pengakuan; 2) peningkatan akses dan kontrol atas sumberdaya hutan; 3) membangun relasi sosio-budaya dan ekonomi serta politik yang lebih adil dan bermartabat. Keywords: Perhutanan Sosial, Masyarakat Adat, Renegosiasi, Pengelolaan Hutan Berbasis Negara, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Abstract The forest management paradigmn in Indonesia has experienced the wave of change that it could be said quite slow if it is compared to another countries. The slow of change is caused by the weakness of sensitivity of the state in responding the dynamics of change at the locality, especially custommary community. The custommary communities who live in or near forest fringe are quaite often to be categorized as a poor, uneducated, lazy, traditional and illegal loggers. But, for some reason, they are also imaged as local people who hold a wise local wisdom: more commit to conservation rather than exploitation, having social instrument to deal with the conflict, commit to social justice and democratisation. The emerge of banditism and the lost of self reliance in managing forest are urgent situation to do deconstruction towards forest managemet paradigmn led by the state. A conceptual approach was used in this normative research. The normative research examined the secondary data, which included primary and secondary legal materials. For the data obtained through normative res earch, instrument to sharpen the discussion was employed using the methods of law interpretation and construction. The deconstruction should be done through renegotiation that emphasis on justice, equity and egality. At least there are three things that should be considered, namely: 1) legalising forest practices done by custommary people; 2) improving 334 accessibility and control over forest resources; 3) developing socio-economic, cultural and politics relation that emphasis on justice, equity and civilisation. Keywords: Social Forestry, Custommary Community, Renegotiation, State Base Forest Management, and Community Base Forest Management 1. PENDAHULUAN Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami gelombang perubahan yang cukup lamban bila dikomparasikan dengan yang terjadi di negara-negara lain, seperti India, Nepal, Philippina. Lambannya perubahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya respon negara terhadap dinamika perubahan yang terjadi di aras lokalitas, khususnya masyarakat adat sebagai masyarakat desa hutan. Bila dilacak dari dimensi historis, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan, baik dari kurun waktu pre kolonial, kolonial, post kolonial, tidaklah cukup signifikan dalam memberikan dampak, baik terhadap kondisi hutan maupun masyarakat (Lihat Peluso, 1992; Simon, 1999; Simon, 2003). Perubahan substansial hanya terjadi pada level tekstual dari kebijakan negara. Perubahan tidak sampai menyentuh esensi dari makna kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan tersebut juga tidak mampu memberikan dampak yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Fakta-fakta di lapangan telah membuktikan dimana marginalisasi masyarakat adat, baik secara budaya, sosial–ekonomi dan politik tetap berlangsung. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat adat tersebut dipaksa harus rela tercerabut dari lebensraum yang selama ini telah menjadi tumpuan hidup mereka. Dari pelacakan sejarah yang dilakukan oleh Peluso (1992); Simon (1999); Simon (2003), membuktikan begitu besarnya hegemoni negara atas sumberdaya hutan. Hutan tetap dipandang sebagai domein negara yang secara absah dapat digunakan menurut spektrum negara. Spektrum masyarakat lokal, terutama masyarakat adat diposisikan sebagai subordinasi dari spektrum negara. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan, baik pada era pre kolonial, kolonial dan post kolonial dalam berbagai bentuknya, seperti statemen politik, peraturan perundang-undangan maupun program dan proyek, cenderung mereduksi kepentingan masyarakat adat. Tulisan ini mencoba mengkaji perubahan kebijakan publik di sektor kehutanan dan berusaha menyingkap makna di balik teks kebijakan tersebut dalam konteks relasi antara negara dengan masyarakat adat. Lebih jauh lagi tulisan ini juga mencoba menyodorkan pilihan alternatif coping strategies masyarakat adat dalam merenegosiasi posisinya terhadap akses dan kontrol atas sumberdaya hutan di aras lokal. 2. TINJAUAN PUSTAKA a. Perubahan Negara dan “Langgengnya” Hegemoni Negara 1). Pre-kolonial Timber extraction atau penambangan kayu dari hutan alam merupakan bentuk pemanfaatan hutan pertama yang dilakukan oleh manusia untuk menikmati sumberdaya anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bangsa yang pertama mengembangkan penebangan kayu dari hutan alam untuk tujuan komersial adalah kerajaan Sumeria di Timur Tengah, yang mulai muncul sekitar tahun 3500 SM. Sumeria adalah kerajaan kedua tertua yang ada di permukaan bumi ini, setelah kerajaan Mesir Kuno yang sudah berkembang sekitar 1500 tahun sebelumnya. Penambangan kayu hanya dilakukan oleh suatu bangsa yang telah mengenal perdagangan, dimana kayu termasuk salah satu komoditi yang diperdagangkan 335 tersebut. Kegiatan utama timber extraction ada tiga, yaitu menebang kayu, mengolah dan menjual (Simon, 2003). Menurut Simon (2003), ketika hutan alam di Eropa hampir habis ditebang, di Pulau Jawa kerajaan Mataram Hindu sedang mencapai puncak kejayaan. Pada abad ke-7 Mataram Hindu telah merancang untuk membangun beberapa candi besar, diantaranya Borobudur (Budha) dan Prambanan (Hindu). Sebagai kerajaan besar, Mataram Hindu telah menjalin dan terlibat dalam jaringan perdagangan internasional, hutan alam jati yang menghasilkan kayu dengan nilai tinggi itu juga mulai dijamah. Timber extraction sebagaimana yang pernah terjadi di Mesopotamia sejak tahun 3500 SM dan di Eropa dari tahun 300 SM hingga abad ke-10 Masehi, akhirnya juga melanda hutan jati di Jawa. Sejak itu, sumberdaya hutan ditempatkan sebagai state property, kemudian diperjelas pada zaman kolonial dan masa pemerintahan Indonesia. Pada zaman kerajaan sumberdaya hutan dikuasai dan dikelola oleh raja sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Hutan oleh kerajaan dilindungi sebab dianggap sebagai tempat keramat bersemayamnya roh-roh halus. Dalam citra spiritual, hutan mempunyai peranan penting dalam ajaran animisme masyarakat. Fungsi ekonomi hutan pada masa kerajaan dinyatakan dengan mengeksploitasi sumberdaya hutan untuk keperluan pembangunan istana kerajaan dan bahan membuat senjata perang. Kerajaan berwenang mengelola sumberdaya hutan melalui tangan-tangan aparatur kerajaan yang ditugaskan di masyarakat (Peluso, 1992; Simon, 2003; Murtijo, 2007). Namun, sehubungan keterbatasan jumlah aparat kerajaan yang ditugaskan untuk memelihara hutan maka pemanfaatan sumberdaya hutan sebagai sumber ekonomi belum optimal. Hutan secara de jure milik kerajaan, akan tetapi de facto masyarakat masih bebas memanfaatkan sumberdaya hutan. Belum ada tindakan secara tegas oleh pemerintah kerajaan untuk menghukum para warga masyarakat yang terbukti mengambil manfaat sumberdaya hutan, meskipun hutan sebagai state property. Hutan ketika itu relatif masih lestari. Masyarakat dan pemerintah kerajaan masih memegang teguh ajaran animisme dan bersama-sama menjaga kesakralan sumberdaya hutan63. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah kerajaan dalam hal pemanfaatan sumberdaya hutan jarang terjadi. 2). Zaman Kolonial Pengusahaan hutan di zaman kerajaan berbeda dengan pengusahaan di zaman kolonial. Hutan di zaman kolonial dimaknai sebagai sumber ekonomi yang wajib dieksploitasi. Pemerintah kolonial Belanda yang pada awalnya berdagang kemudian beralih menjadi kaum penjajah. Kerajaan lokal tunduk kepada pemerintahan kolonial. Akibatnya, kawasan hutan jatuh dalam pengusahaan bangsa penjajah. Hutan dieksploitasi maksimal oleh pemerintah kolonial. Hutan sebagai state property diterapkan secara optimal. Pemerintah kolonial mengelola sumberdaya hutan maksimal untuk mengeruk kekayaan alam daerah jajahan. Berdasarkan pengamatan dari para pedagang Belanda, pulau Jawa memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kemudian mereka membangun serikat dagang pada tahun 1602 dengan nama VOC (Veerenigde Oost Indies Compagnie) dengan kantor berkedudukan di Jayakarta dan digantikan dengan Batavia. Dengan kedudukan kantor pusatnya yang kuat di Batavia, lalu semua kota pesisir dapat dikontrol, mulai dari Banten 63 Hutan dalam budaya Jawa dianggap sebagai tempat yang biadab, sulit dikontrol, dan angker. Hutan dikuasai oleh Dewi Durga sebagai penjaga hutan (Dove, 1985:18-19). Pejabat kerajaan untuk menenangkan pikiran masuk menyendiri ke dalam hutan agar bisa berkomunikasi dengan sang hyang pencipta. Para resi dan tokoh spiritual kerajaan tinggal jauh dari keramaian keraton dan memilih membangun padepokan yang terletak di lereng gunung dalam dan tepi hutan. Hutan dipercayai mempunyai energi sakral yang besar yang mampu mempercepat hubungan batin seseorang dengan sang penguasa alam semesta. Orang sakti zaman kerajaan umumnya bertapa di dalam hutan untuk menghindari interaksi kenikmatan alam duniawi. 336 sa