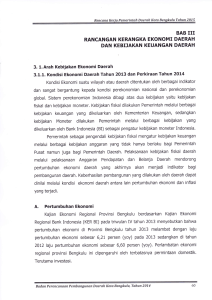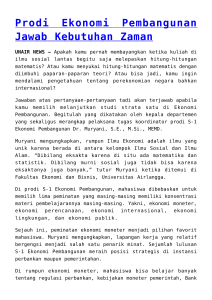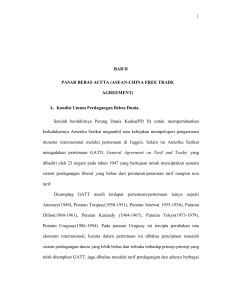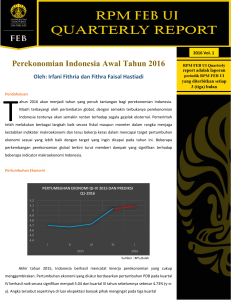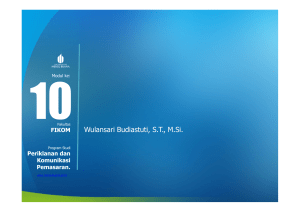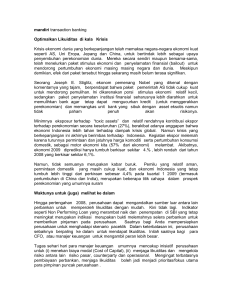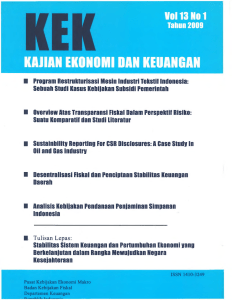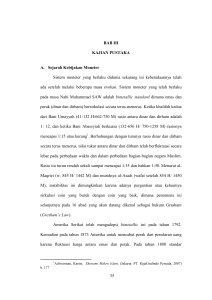Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter
advertisement

Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan Penyunting: Dr. Sri Adiningsih, M.Sc. PENERBIT KANISIUS Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan 072295 © 2012 Kanisius PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI) Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281, INDONESIA Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349 E-mail : offi[email protected] Website: www.kanisiusmedia.com Cetakan keTahun 3 14 2 13 1 12 Editor: FX. Warindrayana Desain isi dan sampul : V. Jaya Supeno ISBN 978-979-21-3313-4 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta SAMBUTAN Studi tentang koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memang selalu menarik untuk terus diikuti. Sebagai dua agen ekonomi yang besar, Pemerintah dan bank sentral dipandang akan dapat mempengaruhi lintasan perekonomian ke depan secara signifikan. Pengaruh keduanya tidak hanya melalui dampak dari masing-masing kebijakan yang ditempuh, namun interaksi kebijakan fiskal dan moneter juga akan berdampak pada perilaku dua agen ekonomi lainnya yaitu rumah tangga dan perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Berangkat dari pentingnya kedua kebijakan tersebut serta berbagai kompleksitas yang dapat muncul dalam proses interaksinya secara tidak langsung maka berimplikasi bahwa pengelolaan kedua kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya perlu berkoordinasi dan saling melengkapi. Kebijakan yang parsial akan memunculkan hasil yang sub-optimal bagi perekonomian. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter setidaknya mencakup dua aspek yang saling melengkapi. Pertama berkaitan dengan upaya mencari titik temu stance kebijakan yang optimal dalam mengelola permintaan agregat dan inflasi. Stance yang longgar dan atau ketat dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu dipadupadankan agar dapat efektif mempengaruhi sasaran akhir. Kedua berhubungan dengan upaya menemukan konfigurasi yang tepat atas komponen/instrumen yang digunakan dalam tiap kebijakan sehingga peran kedua kebijakan dapat saling memperkuat dan tidak saling meniadakan pada saat berinteraksi. Sebagai gambaran dari sisi fiskal, jumlah defisit anggaran dan struktur sumber pembiayaannya akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan likuiditas perekonomian dan inflasi. Belum lagi v pengaruh subsidi di bidang harga yang akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengelola inflasi. Sementara dari kebijakan moneter, arah suku bunga kebijakan moneter akan menentukan potensi defisit anggaran melalui beban bunga yang perlu dibayar dan kemudian berdampak pada menentukan stuktur pembiayaan agar kebijakan fiskal tetap berkesinambungan. Dua aspek koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan makroekonomi baik di domestik dan global. Namun kini, tantangan terasa semakin kompleks karena pasar keuangan global yang semakin terintegrasi terlihat memiliki hubungan timbal balik dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pada satu sisi, prospek kesinambungan fiskal serta konsistensi kebijakan moneter terus dimonitor pelaku pasar keuangan dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang kemudian mempengaruhi stabilitas sistem moneter dan keuangan. Pada sisi lain sebagaimana pengalaman krisis keuangan di AS dan Eropa dalam empat tahun terakhir, sistem keuangan yang memburuk telah membebani kondisi fiskal dan moneter sejalan dengan respon pemerintah dan bank sentral yang terpaksa menyerap risiko di sistem keuangan agar kemerosotan perekonomian lebih dalam dapat dihindari. Buku “Koordinasi Fiskal dan Moneter di Indonesia” ini merupakan kumpulan berbagai tulisan tentang koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Buku ini tidak hanya memaparkan tantangan dalam proses koordinasi kebijakan fiskal moneter di Indonesia dan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Lebih dari itu, buku secara tidak langsung juga mengangkat karakteristik interaksi dan rejim kebijakan fiskal moneter di Indonesia. Pemahaman tentang karakteristik dan rejim kebijakan menurut saya perlu terus kita perdalam karena akan menentukan efektivitas sekaligus meminimalkan kemungkinan munculnya berbagai paradoks pada saat satu kebijakan fiskal dan atau moneter ditempuh. Analisis koordinasi kebijakan seperti pada konsep Unpleasant Monetarist Arithmetic ala Sargent dan Wallace lebih dari tiga dekade lalu dan kemudian berlanjut kepada fenomena vi Fiscal Theory of Price Level sejak dekade 90an merupakan gambaran dari kemungkinan munculnya paradoks kebijakan itu. Oleh karena itu, ISEI mendukung penuh penerbitan buku yang menurut saya sangat bermanfaat ini. Selamat membaca. Jakarta, Februari 2012 Dr. Darmin Nasution vii KATA PENGANTAR “Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal–Moneter: Tantangan ke Depan” adalah merupakan kumpulan tulisan dari para penulis yang memiliki berbagai latar belakang, baik otoritas terkait ataupun mantan otoritas terkait, serta akademisi yang menggeluti dan memiliki keahlian di bidang kebijakan fiskal dan moneter. Tulisan yang disajikan dalam buku ini mencakup sejarah, perkembangan masa kini, studi empiris, masalah dan tantangan yang dihadapi serta perkembangan kedepan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) khususnya Focus Group Koordinasi Fiskal dan Moneter bersama dengan Bank Indonesia menerbitkan kumpulan tulisan ini untuk mengisi kekosongan bahan bacaan yang mengulas koordinasi kebijakan Fiskal dan Moneter. Apalagi pada akhir 2011 seiring dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan akan mengubah pola pengelolaan sistem keuangan dan juga mempengaruhi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu masih banyak pihak di Indonesia yang belum memahami dengan baik koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu diterbitkannya buku ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, akademisi, peneliti ekonomi serta pengambil kebijakan yang ingin memahami dengan lebih baik koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta perkembangannya di Indonesia. Penerbitan buku ini dimungkinkan oleh kerjasama berbagai pihak, khususnya ide dan serangkaian diskusi dari anggota focus group Koordinasi Fiskal Moneter ISEI saudara Rahmat Waluyanto Ph.D., Tony B. Trihartanto Ph.D., Andie Megantara Ph.D., Yoopi Abimanyu Ph.D., Abdul Mongid, dan Dyah Virgoana Gandhi yang telah ikut dalam mempersiapkan penerbitan buku ini serta menyelenggarakan Focus Group Discussion di viii Direktorat Jendral Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan dan di Bank Indonesia. Untuk itu penyunting mengucapkan penghargaaan dan terimakasih atas semua sumbangan pemikiran ataupun tenaga dan dana dalam persiapan hingga penerbitan buku ini. Penghargaan sebesar-besarnya penyunting berikan kepada para penulis yang telah memberikan ijin diterbitkannya tulisannya pada buku ini. Sumbangan tulisan tersebut telah membuat buku ini membahas secara komprehensif berbagai aspek terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter dari berbagai jaman. Secara khusus penyunting juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ketua ISEI Bapak Dr. Darmin Nasution yang telah memberikan dukungan penuh pada penerbitan buku ini. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Laksmi Yustika Devi yang telah memberikan bantuan kepada penyunting dalam proses menyiapkan buku ini sehingga dapat diterbitkannya buku ini. Terimakasih juga penyunting sampaikan kepada Penerbit dan Percetakan Kanisius di Jogjakarta yang telah membantu penerbitkan buku ini. 5 April 2012 Sri Adiningsih ix Tentang Para Penulis Andie Megantara Doktor, Nanzan University, Nagoya-Japan (2003). Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat sebagai Anggota Fokus Grup Koordinasi Fiskal dan Moneter. Angelina Ika Rahutami Doktor, UniversitasGadjahMada (2007). Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Saat ini menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik Soegijapranata. Anggito Abimanyu Ph.D, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (1993). Pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sebagai Sekretaris Umum dan sebagai Ketua Umum PB. Persatuan Bola Basket Indonesia. Pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode tahun 2005 – 2007. x Anwar Nasution Ph.D., Tufts University, Massachussetts, USA (1982). Guru Besar Universitas Indonesia. Pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bambang PS. Brodjonegoro Ph.D., University of Illinois at Urbana-Campaign, Illinois, USA (1997). Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) periode tahun 2004 – 2009. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dwityapoetra S. Besar Ph.D., Cass Business School, City University of London, UK (2010). Financial Economist pada Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia. Pernah ditugaskan sebagai research fellow di wing Stabilitas Sistem Keuangan Bank of England, UK,dan Asian Development Bank Institute, Tokyo, Jepang. Pernah menjadi peneliti pada Centre of Banking Study, di Cass Business School, City Univeristy London, UK. Firman Mochtar M.A., Indiana University, Bloomington, USA (2003). Saat ini menjadi Asisten Deputi Gubernur untuk Kebijakan Moneter. Partisipan dalam 3rd Meeting with Noble Price Winners in Economic Sciences at Lake Constance, Lindau-German pada Agustus 2008 dan Visiting Fellow dalam Monetary and Economic Department di Bank for International Settlement, Basel-Switzerland tahun 2004. xi Gumilang Aryo Sahadewo M.A., Economics, Boston University, Boston, USA (2011). Staf Pengajar dan Peneliti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2009) dan penerima penghargaan dari fakultas yang sama sebagai mahasiswa terbaik (2006). Iskandar Simorangkir Doktor, Universitas Indonesia. Kepala Biro Riset Ekonomi di Bank Indonesia dan Wakil Ketua Dewan Editor Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Saat ini mengajar pada Program Magister Management, Universitas Pelita Harapan dan mengajar mata kuliah Kebanksentralan di beberapa Universitas di Jakarta. Juda Agung Ph.D., Departement of Economics, University of Birmingham, Inggris (1999). Peneliti Ekonomi Utama/Deputi Direktur di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Bank Indonesia. Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi UI sampai sekarang. Sekarang banyak terlibat aktifd alam task force Protokol Manajemen Krisis di tingkat nasional; serta G20 – working group Strong, Sustainable and Balance Growth dan working group capital flows. Pernah menjadi Advisor for Executive Director IMF, dan Staf Gubernur Bank Indonesia. Justina Adamanti Ekonom Junior di Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia. xii Laksmi Yustika Devi M.Si., Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2007). Peneliti ekonomi di Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada. Terlibat di banyak penelitian dalam bidang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, baik yang didanai oleh lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Miranda S. Goeltom Ph.D., Boston University. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Deputi Asisten Menko Ekku Wasbang, Deputi Gubernur Bank Indonesia (1999-2003), Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (2004-2008). Primitiva Febriarti Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2002). Financial system analyst pada Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia. Telah menulis beberapa artikel mengenai perbankan dan stabilitas sistem keuangan, baik yang dimuat di publikasi internal maupun di eksternal Bank Indonesia. R. Maryatmo Doktor, Universitas Gadjah Mada (2004). Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini menjadi Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Periode 2011 – 2014. Sri Adiningsih Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA (1996). Pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Peneliti ekonomi senior di Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada. Aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat sebagai Koordinator Fokus xiii Grup Koordinasi Fiskal dan Moneter dan aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Yogyakarta sebagai anggota Dewan Pertimbangan. Wimboh Santoso Pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York, Amerika Serikat. Wijoyo Santoso Doktor, Universitas Gadjah Mada (2011). Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Studi Ekonomi Makro, Kepala Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia Surabaya, Deputi Direktur Direktorat Statistik Ekonomi-Moneter, Kepala Biro Riset Direktorat Riset-Kebijakan Moneter (DKM), dan Deputi Pemimpin Bank Indonesia Denpasar. xiv DAFTAR ISI SAMBUTAN ............................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................. viii TENTANG PARA PENULIS...................................................... x PENDAHULUAN ...................................................................... 1 DINAMIKA KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DI INDONESIA Sri Adiningsih dan Laksmi Yustika Devi....................................... 13 KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL: TANTANGAN DAN STRATEGI PEMELIHARAAN STABILITAS MAKRO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Miranda Swaray Goeltom............................................................. 43 PERANAN KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Iskandar Simorangkir ................................................................... 83 FISCAL AND MONETARY POLICY INTERACTION: EVIDENCES AND IMPLICATION FOR INFLATION TARGETING IN INDONESIA Firman Mochtar ........................................................................... 111 xv PERANAN ASA NALAR DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN R. Maryatmo................................................................................ 141 INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL: DOMINASI ATAU KAUSALITAS? Angelina Ika Rahutami................................................................. 171 PERAN STIMULUS FISKAL DAN PELONGGARAN MONETER PADA PEREKONOMIAN INDONESIA SELAMA KRISIS FINANSIAL GLOBAL Iskandar Simorangkir dan Justina Adamanti................................. 193 INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI INDONESIA Wijoyo Santoso ............................................................................ 225 PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA Wimboh Santoso dan Dwityapoetra Soeyasa Besar....................... 263 PENTINGNYA PEMELIHARAAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: RISIKO SISTEMIK DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL Wimboh Santoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Primitiva Febriarti 301 MENGINTEGRASIKAN KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL: MENUJU PARADIGMA BARU KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA PASCA KRISIS GLOBAL Juda Agung .................................................................................. 323 xvi PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA Bambang Brodjonegoro dan Andie Megantara ............................. 365 WHAT ASEAN+3 COUNTRIES CAN DO TO REBALANCE THE GLOBAL ECONOMY Anwar Nasution ........................................................................... 391 KOORDINASI FISKAL MONETER DALAM JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Anggito Abimanyu dan Gumilang Aryo Sahadewo....................... 413 INDEKS ...................................................................................... 443 xvii xviii PENDAHULUAN Latar Belakang Koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya fiskal dan moneter menjadi isu penting akhir-akhir ini, karena krisis ekonomi ataupun keuangan semakin sering terjadi, baik di negara maju ataupun sedang berkembang. Sehingga koordinasi kebijakan ekonomi menjadi semakin penting agar kebijakan ekonomi yang diambil dapat efektif mencapai sasaran yang ingin dicapai. Selain itu semakin banyak bank sentral yang independen dari pemerintah, seperti halnya di Indonesia, oleh karena itu menjaga koordinasi fiskal dan moneter semakin tidak mudah dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Gelombang globalisasi yang membuat ekonomi ataupun pasar keuangan terintegrasi pada skala global, membuat arus perdagangan barang dan jasa, modal, investasi dan tenaga kerja semakin meningkat sehingga ekonomi dunia juga berkembang semakin maju. Namun demikian liberalisasi ekonomi telah membuat ekonomi dunia juga semakin komplek dan volatilitas ekonomi ataupun keuangan juga semakin tinggi, sehingga resiko yang dihadapi oleh agen ekonomi semakin meningkat, yang berarti mengelola ekonomi juga semakin tidak mudah. Dengan demikian otoritas ekonomi menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro ataupun sistem keuangan. Oleh karena itu koordinasi fiskal dan moneter yang baik bukan lagi suatu pilihan, tapi keharusan. Meski demikian krisis keuangan global 2008 yang lalu, serta disambung dengan krisis ekonomi Eropa 2010 menunjukkan bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi ataupun ancaman krisis ekonomi kadang diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih luas baik dalam skala beragam kebijakannya (macroprudential) ataupun wilayahnya (antar negara). Koordinasi kebijakan ekonomi internasional kadang diperlukan untuk 1 mengatasi krisis keuangan ataupun ekonomi yang besar. Apalagi pada saat ini, di era demokrasi, tuntutan masyarakat akan kehidupan yang maju, adil dan sejahtera semakin tinggi. Dengan demikian tujuan akhir dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tentunya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya mendapatkan perhatian yang semakin besar, khususnya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu koordinasi dari semua kebijakan baik ekonomi ataupun non ekonomi agar kesejahteraan sosial dapat dicapai. Sementara itu tujuan dari kebijakan ekonomi makro suatu negara adalah tercapainya kondisi ekonomi yang “bebas inflasi” (noninflationary) dan tumbuh stabil (stable growth). Dengan demikian diharapkan tingkat pengangguran dan inflasi rendah dapat dicapai, serta ekonomi bisa tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk itu kebijakan ekonomimoneter dan fiskal yang dilaksanakan oleh bank sentral dan Kementerian Keuangan memegang peranan penting. Meski demikian tujuan dan implikasi dari kedua kebijakan tersebut seringkali saling tidak sama bahkan bertentangan, sehingga dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing kebijakan menjadi tidak optimal, bahkan bisa saling meniadakan. Oleh karena itu, koordinasi antar kedua kebijakan tersebut sangat penting dalam pengelolaan ekonomi, agar bauran kebijakan (policy mix) dapat memberikan dampak optimal dalam perekonomian. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia mengalami evolusi yang menarik. Berkembang mengikuti kondisi ekonomi dan politik, baik domestik maupun internasional. Pada masa Orde Lama, dimana otoritas moneter masih merupakan bagian dari pemerintah, koordinasi fiskal dan moneter tidak menjadi isu penting, karena semuanya ditangan pemerintah hingga 1968, bahkan masih terus berlanjut dengan keberadaan Dewan Moneter hingga tahun 1999 yang lalu. Keberadaan Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, menjadikan kebijakan moneter dan fiskal dipimpin oleh orang yang sama. Sehingga tidak ada masalah koordinasi fiskal dan moneter. Namun dalam perkembangannya, dengan diluncurkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang 2 Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi merupakan bagian dari pemerintah, namun bank sentral yang independen dari pemerintah. Hal tersebut membuat masalah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter muncul, menjadi isu penting dalam pengelolaan ekonomi. Bahkan dalam perkembangannya akhir-akhir ini, sejak krisis keuangan global 2008, dapat dilihat bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik saja tidak cukup meskipun diperlukan, perlu koordinasi kebijakan yang lebih luas, agar resiko sistemik yang dihadapi dalam suatu perekonomian dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu pengelolaan macroprudential diperlukan, bukan hanya antara fiskal dan moneter, namun juga dengan lembaga keuangan keuangan ataupun pasar keuangan lainnya. Oleh karena itu buku ini akan membahas berbagai perkembangan baik secara teoritis, maupun empiris perkembangan koordinasi fiskal dan moneter di Indonesia, demikian juga sejarah, masalah, tantangan dan masa depannya di Indonesia. Sejarah dan Perkembangan Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Sejarah ataupun perkembangan koordinasi kebijakan dan moneter dalam buku ini dapat dibaca dari tulisan Adiningsih dan Devi, serta paper Goeltom. Dimana dari kedua paper tersebut dapat kita lihat bahwa koordinasi fiskal dan moneter di Indonesia mengalami perjalanan yang menarik, dan berkembang semakin kompleks. Dalam perjalanannya, interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal dipengaruhi oleh kondisi politik dan kondisi ekonomi nasional dan juga global. Secara garis besar, sejarah perjalanan interaksi kedua kebijakan tersebut dapat dibedakan menjadi: 1) periode pemerintahan Orde Lama; 2) periode pemerintahan Orde Baru; 3) periode setelah krisis moneter 1997; dan 4) periode setelah krisis finansial global 2008. Sejarah pada masa Orde Lama menunjukkan bahwa meskipun tidak ada masalah dalam koordinasi fiskal dan moneter karena keberadaan Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Namun tidak 3 menjamin stabilitas ekonomi terjaga dengan baik dan ekonomi tumbuh berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang tidak pruden, serta lemahnya pengawasan ataupun pertanggung jawaban kepada publik baik secara langsung ataupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat kebijakan fiskal defisit yang “boros” dimana pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, dibarengi dengan kebijakan moneter yang sangat longgar karena untuk membiaya defisit pemerintah telah membuat inflasi tidak terkendalikan dan ekonomi mandeg. Demikian juga pada masa Orde Baru hingga tahun 1997 menunjukkan bahwa koordinasi fiskal dan moneter yang terjaga dengan baik dengan adanya Dewan Moneter, sehingga stabilitas ekonomi makro cukup terjaga dengan baik, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata sekitar 7,5% per tahun selama hampir tiga dekade, ternyata jika tidak pruden menyimpan potensi krisis ekonomi yang serius. Meskipun kebijakan fiskal “berimbang” (karena utang dari luar negeri dimasukkan sebagai penerimaan pembangunan), disertai dengan deregulasi sektor moneter serta keuangangan lainnya yang luas tanpa pengawasan dan pengaturan yang baik telah menyimpan potensi krisis ekonomi yang serius. Sehingga terjadinya krisis ekonomi Asia yang bermula dari Thailand dengan cepat masuk ke Indonesia. Bahkan akhirnya krisis ekonomi Indonesia adalah yang terparah, terlama dan biayanya termahal di Asia. Sejarah pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa bagusnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidaklah cukup, meskipun diperlukan. Agar supaya optimal dalam mencapai tujuannya, kebijakan fiskal perlu pruden dan kebijakan moneter harus bertanggung jawab, dibarengi dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang baik, serta adanya pertanggung jawaban yang baik terhadap pelaksaan kebijakan moneter dan fiskal. Namun demikian krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa dengan pasar keuangan yang semakin maju, dan banyak produk-produk keuangan canggih bermunculan dipasar serta semakin terintegrasi pasar keuangan global menyebabkan resiko ekonomi yang dihadapi juga semakin 4 besar, volatilitas semakin tinggi dan pasar juga semakin dinamis. Dapat dilihat bahwa pengalaman krisis ekonomi 1997 dan krisis keuangan global 2008, menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berperan penting sebagai langkah antisipasi ataupun mengatasi krisis. Selain itu krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih luas, tidak hanya kebijakan moneter dan fiskal tapi juga dengan otoritas keuangan lainnya agar dampak krisis dapat diminimalkan, bahkan kerjasama internasional juga diperlukan. Meskipun disadari bahwa koordinasi koordinasi kebijakan moneter dan fiskal penting, namun ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang menjadikan interaksi kedua kebijakan ekonomi makro belum optimal. Goeltom dalam papernya menuliskan berbagai kendala yang muncul dalam koordinasi fiskal dan moneter, antara lain terkait dengan hubungan struktural bentuk interaksi kebijakan moneter fiskal itu sendiri. Demikian juga optimalisasi koordinasi kebijakan ekonomi juga menghadapi kendala karena kondisi lingkungan ekonomi dan non ekonomi yang belum menguntungkan, demikian juga aspek teknis dan operasional yang bisa menjadi kendala. Salah satu contoh masalah struktural yang muncul adalah masih digunakannya SBI sebagai instrumen OPT, yang bisa menempatkan kedua kebijakan ekonomi makro tersebut dalam posisi dilematis. Bahkan otonomi daerah juga mengakibatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi tidak optimal. Goeltom juga menuliskan pemikirannya mengenai arah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Diantaranya disampaikan bahwa otoritas moneter maupun fiskal dalam melaksanakan kebijakannya masing-masing dituntut agar lebih transparan, akuntabel, dan terukur, agar dapat memberikan signal yang positif pada pelaku ekonomi. Selain itu juga disampaikan bahwa koordinasi fiskal dan moneter harus berpola pada urutan (sequence) ’tindakan kebijakan’ yang benar, satu otoritas harus mengambil kebijakan terlebih dahulu jika menghadapi tantangan spesifik dalam otoritasnya, kemudian otoritas lainnya meresponnya. Meskipun demikian perlu dijaga agar apapun kebijakan yang dibuat masih dalam kerangka peraturan yang ada. Demikian juga perkembangan ataupun tantangan ekonomi global membuat koordinasi dengan pola ’leader5 follower’ ini harus disesuikan dengan dinamika shocks yang terjadi. Pentingnya Koordinasi Fiskal dan Moneter Berbagai Studi Empiris Dalam beberapa paper dalam buku ini mengulas dengan menarik berbagai hasil studi empiris tentang pentingnya koordinasi fiskal dan moneter di Indonesia. Simorangkir dalam papernya menuliskan perdebatan hubungan kebijakan moneter dan fiskal terkait dengan dampak defisit anggaran yang dapat mengganggu inflasi yang merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Dimana bagi pembuat kebijakan fiskal ternyata kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Oleh karena itu tidak terdapatnya koordinasi diantara kedua kebijakan tersebut dapat berdampak negatip terhadap stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi. Dalam papernya Simorangkir membahas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia dari tahun 1969 hingga tahun 2002 dengan analisis empiris dan menggunakan pendekatan game teori baik berupa cooperative dan non-cooperative game. Dari hasil analisis empiris dan simulasi teori permainan yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal memberikan kerugian output (output loss) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tidak berkoordinasi. Jelas disini dapat disimpulkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting dalam mengelola ekonomi. Sementara itu Mochtar dalam papernya yang berjudul “Fiscal and Monetary Policy Interaction: Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia” meneliti interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Dalam penelitiannya, Mochtar mengestimasi quasi fiscal activities of the central bank (QFA) dan juga assessing fiscal versus monetary dominance aspect. Paper tersebut menemukan bahwa krisis ekonomi 1997 generated QFA di Indonesia. Hal tersebut membuktikan adanya QFA. Dalam paper tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memerankan peranan dominan setelah 1997, meskipun dapat dikatakan dalam skala bentuk yang lemah. 6 Penemuan dalam studi ini menunjukkan implikasi kebijakan bahwa kebijakan moneter di Indonesia memerlukan dukungan disiplin fiskal dan komitmen untuk menjaga keberlanjutannya. Kegagalan untuk mengatasi masalah kinerja fiskal secara optimal dapat menurunkan efektivitas kebijakan moneter dalam mengontrol inflasi dalam inflation targeting framework. Sementara itu Maryatmo dalam papernya menunjukkan bahwa sedikit atau banyak kebijakan defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, kurs, dan tingkat harga (inflasi). Oleh karena itu dalam papernya dia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan defisit anggarannya, karena kebijakan defisit anggaran bukan tanpa biaya yang bisa membawa dampak ekonomi. Maryatmo juga menemukan bahwa ada hubungan timbal balik antara kebijakan defisit anggaran dan variabel moneter. Kebijakan fiskal mempengaruhi instrumen kebijakan moneter, demikian juga kebijakan moneter mempengaruhi instrumen kebijakan fiskal. Dengan demikian hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter dapat bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian independensi Bank Sentral menuntut koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter yang lebih baik. Sehingga dapat tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan yang disertai dengan pengendalian stabilitas moneter. Selain itu Maryatmo juga menunjukkan bahwa para pelakuekonomi dalam melakukan keputusan ekonomi, selain mempertimbangkan yang aktual terjadi di lapangan, juga menggunakan asa nalar. Oleh karena itu dengan asa nalar pelaku ekonomi sangat reaktif terhadap ketidaksesuaian antara informasi awal yang dijanjikan pemerintah dan peristiwa aktual yang mereka alami. Demikian juga dalam papernya, Rahutami menemukan bahwa dengan menggunakan data empiris di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal bersifat kausalitas. Dimana Rahutami menemukan bahwa koordinasi fiskal dan moneter adalah penting karena suku bunga dan uang primer merupakan dua variabel yang harus mendapat perhatian lebih dari Bank Indonesia karena berinteraksi secara kuat dengan anggaran pemerintah. Selain itu juga disarankan agar Bank Indonesia harus 7 menjaga independensinya, karena ternyata kebijakan moneter memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggaran pemerintah dan indikator makro yang lain. Dengan demikian ada keterkaitan antara kebijakan fiskal dan moneter, sehingga koordinasi diantara keduanya penting. Sementara itu Simorangkir dan Adamanti dalam papernya mengkaji dampak stimulus fiskal dan penurunan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan financial computable general equilibrium. Hasil studinya menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis keuangan/ ekonomi, kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan ekspansi moneter sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena munculnya sinergi diantara keduanya, sehingga ekspansi fiskal yang berpotensi meningkatkan suku bunga dinetralisir dengan penurunan suku bunga melalui ekspansi moneter. Kebijakan bauran tersebut lebih efektif dibandingkan apabila hanya dilakukan kebijakan ekspansi fiskal saja atau hanya dilakukan kebijakan ekspansi moneter saja. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa secara komponen PDB, kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan moneter memiliki dampak multiplier yang besar, mampu mendorong permintaan agregat. Sementara itu secara sektoral, hasil studi mereka menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan moneter ternyata meningkatnya produksi di semua sektor ekonomi. Hal ini terjadi karena insentif fiskal (seperti penurunan pajak, penurunan bea masuk impor, dan lainnya) mendorong dunia usaha meningkatkan investasi. Demikian juga, kenaikan permintaan agregat juga mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi peningkatkan permintaan tersebut. Sekali lagi studi ini menunjukkan bahwa koordinasi fiskal dan moneter penting dalam pengelolaan ekonomi, apalagi dalam kondisi krisis ekonomi. Demikian juga Wijoyo Santoso dalam papernya menunjukkan bahwa pada saat menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output, maka koordinasi kebijakan moneter dan fiskal lebih bermanfaat (dibandingkan tanpa koordinasi), khususnya untuk mengurangi kerugian sosial. Demikian juga dari hasil simulasi yang dilakukannya menunjukkan adanya koordinasi 8 kebijakan moneter dan fiskal (kebijakan fiskal endogen) menghasilkan kerugian yang lebih kecil dibandingkan tanpa koordinasi (kebijakan fiskal eksogen). Bahkan Santoso menyarankan perlunya peningkatkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui penguatan kelembagaan seperti adanya semacam Dewan Moneter. Koordinasi Fiskal dan Moneter dan Perkembangannya Kedepan Sebelum berbagai perkembangan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terbaru ataupun kedepan disajikan dalam beberapa paper dalam buku ini, penyunting ingin pembaca memahami perkembangan sektor keuangan di Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis dulu agar dapat memahami perkembangan sektor keuangan dengan baik. Untuk itu tulisan Wimboh Santosa dan Dwityapoetra Soeyasa Besar bisa menjadi bacaan yang menarik. Mereka menunjukkan perkembangan sektor keuangan Indonesia yang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan aliran modal asing. Mereka menunjukkan bahwa ketahanan pelaku di pasar keuangan khususnya perbankan cukup tinggi akhir-akhir ini, namun derasnya modal asing yang masuk menyebabkan potensi kerapuhan pasar keuangan tinggi. Oleh karena itu perlu inovasi dan pendalaman pasar keuangan agar supaya stabilitas sektor keuangan dapat terjaga dengan baik. Demikian juga berbagai rambu dan standar kehati-hatian yang membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh pelaku di sektor keuangan perlu ditingkatkan Beberapa paper selanjutnya menganalisis tentang perkembangan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pada masa kini dan kedepan, yang perlu menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan pasar keuangan yang semakin kompleks. Wimboh Santoso, Dwityapoetra S. Besar dan Primitiva Febriarti dalam papernya menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter saja sudah tidak memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal. Dalam papernya mereka menyampaikan bahwa salah satu pelajaran berharga dari krisis keuangan global lalu adalah perlunya kerangka kebijakan yang memiliki jangkauan luas guna menjaga kestabilan 9 sistem keuangan, dengan kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut diperlukan guna meminimisasi risiko keuangan yang bersifat sistemik, yang bisa membahayakan perekonomian. Untuk itu bank sentral sebagai lembaga yang memiiliki piranti dan keahlian diharapkan untuk diberikan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Agung dalam papernya menuliskan bahwa krisis ekonomi global 2008 memberikan pelajaran bahwa kemampuan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro semakin terbatas, sumber instabilitas ekonomi makro semakin banyak bersumber dari sektor keuangan. Agung membuka wacana bagi paradigma baru kebijakan moneter di Indonesia pasca krisis global, dengan mengintegrasikan kebijakan makroprudensial dalam kebijakan inflation targeting. Sementara itu dalam papernya, Brodjonegoro dan Megantara menguraikan bahwa dinamika dan perkembangan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diterapkan, sesuai dengan tiga fungsi utamanya yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran negara. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir berupaya merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment, dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga mereka menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang baik dan sehat akan menciptakan sustainabilitas fiskal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nasution dalam papernya yang berjudul “What ASEAN+3 Countries Can Do to Rebalance the Global Economy”, menyampaikan tentang peran yang dapat dilakukan oleh negara ASEAN+3 untuk membantu mengatasi masalah ekonomi global yang tidak berimbang (pada akhirnya juga membantu menjaga stabilitas ekonomi global) karena memiliki cadangan devisa yang besar, ekonomi nya besar, dinamis dan tumbuh pesat, juga secara regional memiliki berbagai mekanisme untuk menjaga stabilitas kawasan seperati dengan adanya Chiang Mai Initiatives (CMI). Paper Nasution menunjukkan bahwa perlunya koordinasi internasional ataupun 10 kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Sementara itu Abimanyu dan Sahadewo dalam papernya menuliskan bahwa sektor keuangan yang kuat merupakan fondasi pembangunan ekonomi, namun demikian sensitif terhadap gejolak ekonomi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu mereka percaya bahwa jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) memiliki peran signifikan untuk stabilitas di sektor keuangan, khususnya bisa dijadikan landasan hukum dalam penanganan sektor keuangan di saat krisis. Sehingga juga bisa membentuk asa positip bagi pelaku ekonomi, baik rumah tangga dan perusahaan. Dalam papernya mereka menyampaikan bahwa kerangka JPSK harus meliputi kerangka kerja dan kerangka hukum Komite Stabilisasi Sektor Keuangan dan juga Komite Koordinasi. Mereka menganggap bahwa kedua komite tersebut sangatlah penting agar koordinasi kebijakan di masa krisis dan penanganan lembaga keuangan yang bermasalah dapat segera dilakukan, tanpa harus melewati birokrasi yang panjang, misalnya karena harus melapor pada legislatif. Selain itu mereka juga menyampaikan bahwa koordinasi fiskal dan moneter juga penting dalam mengelola ekonomi dalam kondisi normal. Dimana tingkat inflasi akan lebih optimal dicapai jika berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait kebijakan fiskal yang akan ditempuh. 11 12 DINAMIKA KOORDINASI KEBIJAKAN FISKALMONETER DI INDONESIA Sri Adiningsih dan Laksmi Yustika Devi Latar Belakang Salah satu isu yang banyak menyita perhatian masyarakat dunia, ataupun suatu bangsa pada saat ini adalah ekonomi. Hal tersebut didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang membuat kemajuan di manapun juga di dunia ini bisa dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas, membuat tuntutan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera ataupun maju semakin meningkat. Padahal meskipun globalisasi telah membuat ekonomi dunia berkembang semakin pesat, namun juga menghadapi volatilitas yang semakin tinggi. Krisis ekonomi ataupun keuangan semakin sering datang dan pergi dalam dua dekade terakhir ini. Sehingga mengelola ekonomi suatu negara semakin tidak mudah, semakin kompleks, dan tantangan serta ancamannya juga semakin besar. Sehingga koordinasi kebijakan ekonomi pun menjadi semakin penting, namun semakin tidak mudah dilakukan. Selain itu perkembangan krisis global 2008 yang berasal dari subprime mortgage di Amerika Serikat ataupun krisis ekonomi Eropa 2010 menunjukkan bahwa untuk mengatasi krisis keuangan/ekonomi ataupun ancaman krisis ekonomi kadang diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih luas. Koordinasi kebijakan ekonomi secara internasional bahkan diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi yang besar, seperti krisis keuangan 2008 yang lalu. Dari berbagai kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi makro memegang peranan yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro ataupun pengelolaan ekonomi suatu negara. 13 Tujuan dari kebijakan ekonomi makro suatu negara adalah tercapainya kondisi ekonomi yang “bebas inflasi” (noninflationary) dan tumbuh stabil (stable growth). Dalam kondisi ini, fluktuasi pada tingkat pengangguran, produksi, dan harga dapat diminimalkan dan pertumbuhan potensial pada output rill dapat tercapai. Kebijakan makroekonomi terdiri atas dua instrumen utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Tujuan dan implikasi dari kedua kebijakan tersebut seringkali saling bertentangan. Perbedaan tujuan tersebut dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing kebijakan menjadi tidak optimal atau bahkan saling meniadakan (set-off) (Goeltom, 2007). Oleh karena itu, amatlah penting untuk memiliki suatu mekanisme koordinasi antar kedua otoritas kebijakan atau strategi bauran kebijkan (policy mix) agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Blinder (1982) dalam Goeltom (2007) menyatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi makin penting ketika terdapat ketidakpastian yang tinggi dari pengaruh masing-masing kebijakan. Kondisi ini dialami oleh banyak negara maju dan emerging countries pada awal tahun 2000-an, saat perekonomian dunia menunjukkan kelesuan yang berlanjut. Ketika itu, kebijakan yang diambil masih memberikan ketidakpastian yang cukup tinggi sementara tingkat suku bunga sudah ditekan hingga amat rendah. Kebijakan yang dilakukan secara parsial dan bertahap cenderung akan makin meningkatkan ketidakpastian sehingga penurunan kinerja perekonomian terus berlangsung. Oleh karena itu, Mohanty dan Scatigna (2004) dalam Goeltom (2007) menyatakan bahwa banyak ahli ekonomi yang menyarankan strategi yang sebaiknya ditempuh dalam situasi tersebut adalah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta penggunaan berbagai instrumen kebijakan secara lebih agresif untuk mendukung efektivitas kebijakan yang diambil. Pada akhirnya, kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal tidak dapat berjalan sendiri. Dalam prakteknya, yang sering dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi-konsekuensi moneter atau kebijakan moneter dengan konsekuensi-konsekuensi fiskal (Boediono, 14 2001). Hal ini digarisbawahi pula oleh Krugman dalam Corsetti dan Mueller (2008) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efisien bila dibarengi dengan kebijakan moneter yang akomodatif. Dengan kata lain, agar stimulus fiskal dapat berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang konsisten dengan mandat menjaga kestabilan harga. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia sejak merdeka hingga kini mengalami dinamika yang luar biasa. Indonesia mengalami masa-masa dimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidak diperlukan karena memang telah menyatu, namun dalam perkembangannya koordinasi kebijakan tersebut menjadi semakin penting karena mulai 1999 bank sentral di Indonesia independen dari pemerintah, bukan merupakan bagian dari pemerintah lagi. Bahkan dalam perkembangannya akhir-akhir, dimana sistem keuangan menjadi semakin kompleks, sehingga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, perlu adanya koordinasi kebijakan ekonomi yang lebih luas. Pasang Surut Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia Dalam perjalanannya, interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi nasional dan juga global. Secara garis besar, sejarah perjalanan interaksi kedua kebijakan tersebut dapat dibedakan menjadi: 1) periode pemerintahan Orde Lama; 2) periode pemerintahan Orde Baru; 3) periode setelah Krisis Moneter 1997; dan 4) periode setelah Krisis Finansial Global 2008. 1. Periode Pemerintahan Orde Lama Pada tahun 1828, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. DJB kemudian diputuskan sebagai bank sentral pada 15 penyerahan kedaulatan Indonesia pada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Beberapa waktu setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dilakukan nasionalisasi terhadap DJB melalui UndangUndang Nasionalisasi DJB pada tanggal 6 Desember 1951. Kemudian, di tahun 1953, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Dua hal penting dari diberlakukannya undang-undang tersebut adalah (Bank Indonesia, 2007a): 1. Pendirian sebuah bank dengan nama “Bank Indonesia” sebagai pengganti DJB dan berfungsi sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia seperti yang tertulis dalam undang-undang tersebut di antaranya adalah mengatur nilai satuan uang Indonesia dan menjaga agar nilai itu seimbang (stabil) serta menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia 2. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat Hambatan terbesar dari diberlakukannya undang-undang tersebut adalah dibentuknya Dewan Moneter yang menjadi salah satu pimpinan Bank Indonesia (BI). Sjafruddin Prawiranegara selaku Presiden DJB terakhir dan juga Gubernur BI pertama berpendapat bahwa keikutsertaan Dewan Moneter sebagai salah satu pimpinan BI menjadikan BI tidak independen dari pemerintah. Hak BI untuk mencetak dan mengedarkan uang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Sjafruddin mengemukakan bahwa hal yang lebih tepat dilakukan adalah membentuk Dewan Koordinasi yang beranggotakan wakil pemerintah dan wakil direksi bank dan berada di luar struktur kepemimpinan bank sentral. Dengan demikian, bank sentral tidak dapat diintervensi terlalu jauh oleh pemerintah dan sebaliknya bank sentral juga tidak terlalu independen dari pemerintah. Namun, format tersebut tidak pernah terwujud. Secara formal, keberadaan Dewan Moneter tetap dipertahankan hingga tahun 1968 (Bank Indonesia, 2007a). Dewan Moneter beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI. Ketua Dewan Moneter adalah Menteri 16 Keuangan yang dapat digantikan oleh Gubernur BI bila ia berhalangan. Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 hari sekali atau lebih bila anggota yang memiliki hak suara menginginkannya. Tugas Dewan Moneter adalah menetapkan kebijakan moneter umum yang akan dilaksanakan oleh BI serta memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijakan BI dalam urusan lainnya, seperti misalnya dalam menetapkan tarif bunga bank. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Moneter dibantu oleh Dewan Penasehat. Dewan Penasehat memiliki tugas untuk memberikan nasehat-nasehatnya bagi Dewan Moneter baik diminta ataupun tidak dan membahas segala permasalahan Dewan Moneter dengan maksud agar dewan ini dapat menetapkan kebijakan secara optimal berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat. Sementara tugas direksi dalam BI adalah (UU No. 11 Tahun 1953)1: 1. menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter; 2. menyelenggarakan pemberian kredit oleh BI, terutama untuk pemberian dan perpanjangan kredit dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan kredit-kredit tersebut, juga untuk menghentikan kredit yang sedang berjalan, dan menolak pemberian kredit; dan 3. menyelenggarakan segala pekerjaan BI yang lain, dengan memperhatikan petunjuk Dewan Moneter. Dengan demikian, peran BI dalam pelaksanaan kebijakan moneter tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah melalui Dewan Moneter (Bank Indonesia, 2007a). UU No. 11 Tahun 1953 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Pemerintah yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri. Contoh realisasi dari tanggung jawab ini adalah saat pemerintah mengumumkan persetujuan keputusan rapat Dewan Moneter pada tanggal 18 Juni 1957, yaitu mengadakan perimbangan 1 Keseluruhan isi UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia diakses dari http:// hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_1953.htm pada 5 Desember 2011. 17 ekspor dan impor, memperbaiki persediaan devisa dengan meningkatkan ekspor, serta menyederhanakan peraturan devisa guna mengatasi kesulitankesulitan di bidang moneter, keuangan, dan perekonomian (Bank Indonesia, 2007a). Prawiro (1998) mencatat bahwa pelaksanaan kebijakan moneter pada periode Orde Lama cenderung dipengaruhi oleh kondisi politik. Pemerintah Orde Lama menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif yang berujung pada defisit anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut dipicu oleh: 1. Pengeluaran Militer Aksi pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 dan konfrontasi terhadap Malaysia di tahun 1963, serta aksi-aksi militer domestik untuk menumpas beberapa kerusuhan dan pemberontakan menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk militer meningkat pesat dan menguras sumber daya negara yang terbatas. 2. Impor Beras Kekurangan pasokan beras dialami masyarakat pada tahun 19571965. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia yang menyebabkan cadangan devisa negara terkuras. Impor beras terus dilakukan karena penghentian impor menyebabkan masyarakat panik sehingga memperparah inflasi yang sudah tinggi. 3. Subsidi Sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, pemerintah menyediakan subsidi besar terhadap banyak barang konsumsi, khususnya produkproduk minyak dan beras. Pada tahun 1965, lebih dari seperlima penghasilan pemerintah dialokasikan untuk mensubsidi produkproduk minyak. 4. Proyek Mercu Suar Pembangunan monumen publik, yaitu Monumen Nasional, dan proyek-proyek besar lainnya, seperti gedung-gedung dan stadion olah raga yang megah. 18 5. Dana Bebas (Discretionary Funds) Departemen dan proyek-proyek dapat memperoleh dana yang besarnya tergantung kebijaksanaan presiden. Defisit anggaran tersebut kemudian dibiayai dengan pinjaman dari BI. Uang yang beredar meningkat tajam jauh melebihi kebutuhan riil perekonomian sehingga mendorong melambungnya harga. Akibatnya, inflasi menjadi tidak terkendali hingga mencapai 635% pada tahun 1966. Keadaaan ini dikenal dengan periode hiperinflasi. Ekonomi Indonesia dapat dikatakan mandeg, tidak tumbuh (PPSK BI, 2003). Kondisi buruk perekonomian sejak awal kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960an tersebut memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian (pruden) dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal harus mampu mengendalikan defisit anggaran dengan cara menyeleksi pengeluaran anggaran dan memberi prioritas pada jenis-jenis pengeluaran yang mampu mendorong kegiatan ekonomi riil. Pengeluaran-pengeluaran yang cenderung kurang strategis dan berlebihan harus dihindarkan. Kedua, kebijakan moneter tidak boleh dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran. Pengendalian inflasi harus tetap menjadi fokus kebijakan moneter. Membiayai defisit anggaran dengan mencetak uang akan mengancam kestabilan harga dan kestabilan moneter secara keseluruhan. Ketiga, perlu adanya koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi (PPSK BI, 2003). Pengalaman masa Orde Lama menunjukkan bahwa meskipun tidak ada masalah dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter karena pengambilan kebijakan berada dalam kewenangan Menteri Keuangan yang juga sebagai ketua Dewan Moneter. Namun kebijakan yang tidak pruden dan tidak bertanggung jawab serta lemahnya pengawasan telah membuat kebijakan fiskal defisit (“boros”) dimana pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, dibarengi dengan kebijakan moneter yang tidak bertanggung jawab telah membuat inflasi tidak terkendalikan dan ekonomi mandeg. 19 2. Masa Pemerintahan Orde Baru Pada tanggal 3 Oktober 1966, untuk mengatasi kondisi hiperinflasi, pemerintah secara resmi meluncurkan program stabilisasi. Intisari dari program tersebut terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diambil adalah (Prawiro, 1998): 1. Kebijakan Fiskal Pemerintah menerapkan anggaran berimbang dengan cara menghentikan proyek-proyek yang tidak produktif dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pemerintah juga melakukan reorganisasi dalam sistem perpajakan yang kuno dan tidak efisien. 2. Kebijakan Moneter Pemerintah menerapakan kebijakan moneter yang agak paradoks, yaitu kebijakan uang ketat (termasuk kredit ketat) yang dibarengi dengan kebijakan kredit longgar pada jenis investasi yang diseleksi, seperti rehabilitasi dari fasilitas-fasilitas yang telah tersedia atau proyek-proyek yang memiliki potensi paling besar untuk memperluas kapasitas produksi negara. Disiplin dalam pelaksanaan kebijakan fiskal mensyaratkan pemerintah untuk mengendalikan pengeluarannya secara menyeluruh. Pada bulan Desember 1966, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan anggaran pertama pemerintah Orde Baru. Dokumen-dokumen anggaran menyatakan anggaran tahun 1967 sebagai “Anggaran Berimbang” yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibatasi oleh pendapatan pemerintah sehingga defisit ditiadakan sebanyak mungkin. Sebuah Keputusan Presiden yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1966 mewajibkan pemerintah untuk memberi laporan kuartalan tentang anggaran yang telah diwujudkan yang juga mencatat setiap utang dan piutang. Laporan ini berkembang menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap setengah tahun untuk kemudian diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Prawiro, 1998). 20 Sementara untuk kebijakan moneter, pemerintah yang baru mulai memberikan fleksibilitas di sektor perbankan dengan memberlakukan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Berdasarkan undang-undang ini, tugas BI adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu2: 1. mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah; dan 2. mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Keberadaan Dewan Moneter di BI masih tetap dipertahankan. Namun, Dewan Moneter tidak lagi bertindak sebagai salah satu pimpinan BI. Tugas Dewan Moneter berdasarkan undang-undang tersebut adalah3: 1. membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan mutu taraf hidup rakyat; 2. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan BI melaksanakan kebijakan moneter tersebut sesuai dengan keputusan Dewan Moneter. Keberadaan Dewan Moneter dalam BI mempunyai nilai positif karena dengan demikian kebijakan moneter dapat terintegrasi dan terkoordinir dengan kebijakan fiskal dan kebijakan makro lainnya. Namun, di sisi lain, hal ini mengaburkan fokus tugas, disiplin, dan tanggung jawab masingmasing instansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Lebih jauh, keberadaan pemerintah dalam BI masih memungkinkan dimanfaatkannya kebijakan moneter untuk pembiayaan fiskal sehingga prinsip kehati-hatian dan disiplin kebijakan ekonomi makro kurang dapat terjamin (PPSK BI, 2003). 2 3 Keseluruhan isi UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diakses dari http://www.sjdih. depkeu.go.id/fullText/1968/13Tahun~1968UU.htm pada 5 Desember 2011 Ibid 21 Pada tahun 1968 juga pemerintah berusaha mendorong produksi dengan menggalakkan investasi dalam negeri dan luar negeri. Undangundang penanaman modal dalam negeri dan asing disusun dalam bentuk UU PMA dan UU PMDN. Di tahun yang sama, pemerintah mulai mendirikan pasar modal yang ditujukan untuk meningkatkan peranan sektor keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Namun demikian, lembaga-lembaga keuangan tersebut masih belum berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan pada saat itu masih amat sederhana. Konsekuensinya, kebijakan keuangan yang diterapkan juga sangat terbatas (Nopirin, 1996). Dalam perkembangannya, investasi baik dari dalam maupun luar negeri meningkat sehingga produksi barang bertambah. Jumlah uang dapat dikendalikan melalui pelaksanaan anggaran berimbang dan produksi barang meningkat sehingga tingkat inflasi dapat terkendali. Inflasi menurun dari 635% di tahun 1966 menjadi 10% tahun 1969 dan bahkan hanya 2,5% di tahun 1971. Program stabilisasi yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan berhasil memperbaiki kondisi perekonomian (Nopirin, 1996). Di pertengahan tahun 1970, harga minyak di pasaran dunia meningkat hingga hampir empat kali lipat. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Positif karena hasil dari minyak meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari sisi fiskal. Negatif karena peningkatan penerimaan devisa hasil minyak dan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar dari sisi fiskal. Kondisi ini mengharuskan kebijakan moneter untuk melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal tersebut agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian yang dapat meningkatkan inflasi (PPSK BI, 2003). Pada tahun 1974, dari sisi moneter, pemerintah mulai melaksanakan kebijakan kredit selektif. Hal ini dilakukan agar jumlah uang beredar tetap terkendali sehingga inflasi dapat tetap terjaga. Setiap tahun BI menyusun rencana ekspansi kredit secara nasional dengan menghitung jumlah 22 uang beredar yang sesuai dengan perkiraan laju inflasi dan pertumbuhan output. Pagu kredit setahun ke depan bagi masing-masing bank ditetapkan berdasarkan rencana kredit yang disampaikan oleh tiap bank kepada BI sebelumnya. Pagu individual bank tersebut pada akhirnya akan menjadi dasar untuk penyaluran kredit likuiditas yang disediakan BI sesuai dengan sektor/program yang sudah ditetapkan (PPSK BI, 2003). Di tahun 1981-1982, kondisi ekonomi dunia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan perdagangan antar negara maju. Amerika mengalami dobel defisit, yaitu defisit anggaran belanja dan defisit neraca pembayaran, yang berujung pada langkah proteksi. Kondisi resesi dan aksi proteksi tersebut merupakan hambatan bagi ekspor Indonesia. Akibatnya, dana pemerintah untuk pembangunan ekonomi menjadi terbatas. Pemerintah kemudian melakukan serangkaian kebijakan penyesuaian untuk menghadapi situasi tersebut, seperti devaluasi, penjadwalan proyek, dan kebijakan yang terpenting adalah kebijakan deregulasi perbankan (Nopirin, 1996). Kebijakan deregulasi perbankan diberlakukan pada 1 Juni 1983. Inti dari kebijakan yang lebih dikenal dengan sebutan PAKJUN 1983 ini adalah (Bank Indonesia, 2007b): 1. Bank pemerintah diberi kebebasan untuk menetapkan suku bunga deposito, sebelumnya suku bunga deposito ini masih diatur oleh BI; 2. Ketentuan pagu kredit, yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi langsung, dihapuskan. Sebagai gantinya, bank sentral menggunakan instrumen tidak langsung yaitu penentuan cadangan wajib, operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto, dan moral suasion. Sejak kebijakan ini diberlakukan, BI mengendalikan moneter dengan menggunakan instrumen tidak langsung. Mekanisme dan instrumen pengendalian moneter berubah. Pemerintah tidak lagi melakukan intervensi langsung dalam mengendalikan kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka (open market operation) dilakukan dengan menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto sejak bulan 23 Februari 1984. SBI merupakan instrumen moneter tidak langsung yang digunakan untuk menyedot kelebihan uang beredar di masyarakat jika kondisi moneter terlalu ekspansif. Perbankan dapat memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki dengan membeli SBI jika dana tersebut tidak dipinjamkan ke masyarakat. Pengendalian likuiditas juga dibantu dengan intervensi di pasar uang rupiah dengan cara memberi pinjaman jangka pendek antara overnight hingga tujuh hari. Sebaliknya, untuk menambah uang beredar, sejak tanggal 1 Februari 1985, BI menerbitkan pula instrumen OPT baru berupa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Setelah kebijakan deregulasi tersebut diberlakukan, sektor perbankan dan keuangan di Indonesia berkembang pesat. Bukan hanya terlihat dari jumlah bank yang beroperasi, besarnya dana masyarakat yang dapat dimobilisasi baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, tetapi juga dalam bentuk kredit dan jenis pembiayaan lainnya yang disediakan oleh perbankan untuk dunia usaha. Pasar keuangan juga berkembang pesat baik dari sisi volume transaksi keuangan maupun bertambahnya variasi produk keuangan (saham, obligasi, surat-surat berharga, dan produk-produk derivatif ) yang diperdagangkan. Akibatnya, semakin banyak dana yang berputar di sektor keuangan dan hubungan antara uang, inflasi, dan ouput semakin erat dibandingkan dengan periode sebelumnya (PPSK BI, 2003). Pemerintah pun kemudian menyadari bahwa tidak bisa mengandalkan penerimaan dari minyak saja. Untuk itu, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan dari pajak dengan memberlakukan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ada empat tujuan pokok dari UU pajak yang baru, yaitu (Prawiro, 1998): 1. penyederhanaan, pembayar pajak umumnya harus dapat menentukan dengan jelas dan pasti apa yang merupakan kewajiban pajaknya tanpa mempergunakan seorang ahli pajak atau tanpa perlu menghubungi petugas-petugas dari bagian perpajakan; 2. pemerataan, sistem perpajakan harus mambawa pemerataan bagi semua penduduk; 24 3. harus dapat ditegakkan (enforceable), sistem perpajakan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga pajak dengan mudah dapat dikumpulkan; dan 4. meningkatkan pendapatan, sistem baru ini harus dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. UU ini mulai diberlakukan pada tahun 1984. Sebelum UU diberlakukan, sekitar 30% dari pajak yang diterima berasal dari sumbersumber non migas. Dua tahun kemudian, pada tahun 1986-1987 ketika Indonesia menghadapi krisis harga minyak yang jatuh, sistem perpajakan baru sudah mulai berjalan dengan lancar. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan persentase porsi pajak dari sumber-sumber non migas menjadi 61%. Sistem pajak yang baru berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak perusahaan dan perorangan. Pendapatan non migas pemerintah meningkat pesat. Sebagai gambaran, pendapatan pemerintah dari pajak (tax revenue) Indonesia dibandingkan dengan PDB di tahun 1990 adalah 17,8%; sama dengan persentase yang dicapai Malaysia, sementara tax revenue Singapura dan Thailand masing-masing adalah 14,6% dan 16,6% (Asian Development Bank, 2011). Kebijakan penting lainnya yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 1983 adalah menempatkan rupiah dalam sistem “crawling peg”, yaitu sistem nilai tukar mengambang dengan rentang fluktuasi yang diredam untuk memelihara nilai tukar yang stabil. Saat harga minyak kembali jatuh di tahun 1986, pemerintah mendevaluasi rupiah dengan penurunan nilai sebesar 31%. Cara ini mampu mengendalikan inflasi. Rata-rata inflasi di bawah 7% sepanjang tahun 1986-1989 setelah devaluasi sebesar 31% merupakan pencapaian yang luar biasa. Faktor utama yang berperan dalam rendahnya inflasi adalah pengendalian ketat terhadap pasokan uang, pengendalian fiskal, dan koordinasi yang baik antara BI dan bank-bank negara lainnya. Devaluasi di tahun 1986 merupakan devaluasi Indonesia yang terakhir karena sejak itu rupiah diatur dengan sistem “managed float”, yaitu sistem nilai tukar mengambang tapi terkendali terhadap mata uang asing (Prawiro, 1998). 25 Di tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang pada intinya merupakan paket penyempurnaan kebijakan-kebijakan sebelumnya di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Langkah-langkah yang ditempuh, di antaranya, adalah penurunan cadangan minimum dari 15% menjadi 2% dan pemberian kelonggaran ijin pendirian bank-bank baru dan bank campuran. Akibatnya, sektor perbankan dan keuangan di Indonesia berkembang sangat pesat (PPSK BI, 2003). Paket Kebijakan 27 Oktober diikuti dengan pelaksanaan Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 yang bertujuan meningkatkan pengerahan dana masyarakat melalui pengembangan pasar modal, lembaga pembiayaan dan asuransi. Pihak swasta diberikan kesempatan lebih luas untuk menyelenggarakan bursa efek atau pasar modal, usaha asuransi dan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Sebagai dampak dari liberalisasi di sektor keuangan dengan diberlakukannya paket-paket kebijakan tersebut, aliran dana yang masuk ke perekonomian Indonesia, khususnya pinjaman luar negeri swasta, meningkat sangat besar dan pesat. Di satu sisi, besarnya aliran dana luar negeri tersebut dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, aliran dana luar negeri tersebut juga menimbulkan sejumlah masalah. Dana luar negeri tersebut pada umumnya berupa pinjaman luar negeri swasta, berjangka pendek, tidak memperhitungkan resiko perubahan nilai tukar, dan banyak dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek swasta yang berjangka panjang dan tidak menghasilkan devisa. Dari sisi moneter, besar dan mobilitas aliran dana luar negeri tersebut juga mempersulit pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI (PPSK BI, 2003). Untuk menghindari dampak negatif dari membanjirnya aliran dana luar negeri tersebut, BI melakukan penyerapan kelebihan likuiditas sehingga mendorong kenaikan suku bunga dalam negeri. Namun, kenaikan suku bunga ini malah makin meningkatkan masuknya aliran dana luar negeri, khususnya dalam bentuk surat-surat berharga berjangka pendek. Akibatnya, jumlah pinjaman luar negeri swasta dalam berbagai bentuk dan 26 jangka waktu semakin membesar. Kondisi ekonomi juga diperburuk dengan tidak dijalankannya proyek-proyek swasta yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat (good corporate governance). Hal inilah yang menjadi penyebab utama dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia di tahun 1997 (PPSK BI, 2003). Tarmidi (1999) menyatakan bahwa krisis ekonomi 1997 diperparah oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar intervensi terbatas. Sistem nilai tukar tersebut menyebabkan terjadinya apresiasi nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi ketika dihapus pada tanggal 14 Agustus 1997. Pemerintah terkesan tidak memiliki kebijakan yang jelas dan terperinci untuk mengatasi krisis. Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan cepat. Pengalaman masa Orde Baru hingga munculnya krisis ekonomi 1997 menunjukkan bahwa koordinasi fiskal dan moneter yang terjaga dengan baik, sehingga secara umum stabilitas ekonomi makro terjaga dengan baik, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata sekitar 7,5% per tahun, ternyata menyimpan potensi krisis ekonomi yang serius. Kebijakan fiskal yang “berimbang”, namun dengan catatan bahwa utang dari luar negeri dimasukkan sebagai penerimaan pembangunan, disertai dengan deregulasi sektor moneter tanpa pengawasan dan pengaturan yang baik telah menimbulkan permasalahan ekonomi yang besar Demikian juga masuknya dana asing jangka pendek yang besar jika tidak dikelola dengan baik menimbulkan resiko yang besar, capital outflow yang besar dalam jangka pendek. Sehingga krisis ekonomi yang bermula dari Thailand dengan cepat masuk ke Indonesia dan menyebabkan ambruknya ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia adalah yang terparah, terlama dan biayanya termahal di Asia. 27 3 . Periode Setelah Krisis Ekonomi 1997 Krisis tahun 1997 berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mencegah hancurnya sektor perbankan, dana sangat besar disuntikkan oleh pemerintah (melalui BI) ke sektor ini, yang kemudian memicu kenaikan laju inflasi. Di sisi lain, BI harus menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat dengan memberlakukan kebijakan moneter kontraktif, yang kemudian menyebabkan naiknya suku bunga dan secara umum menimbulkan persoalan lain di pasar keuangan (PPSK BI, 2003). Resep umum yang diterapkan oleh negara-negara di Asia dalam menghadapi krisis adalah menjaga kestabilan makroekonomi dengan cara (Sabirin, 2000): 1. Di bidang moneter: memberlakukan kebijakan moneter ketat yaitu kebijakan moneter untuk mengurangi penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal yang berlebihan; 2. Di bidang fiskal: mengurangi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif dan mengalihkannya pada pengeluaran untuk kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi biaya sosial akibat krisis ekonomi; 3. Di bidang pengelolaan dunia usaha (corporate governance): memberlakukan kebijakan yang akan memperbaiki kemampuan pengelolaan baik di sektor publik atau swasta. Termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi intervensi pemerintah, monopoli dan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif lainnya; 4. Di bidang perbankan: memberlakukan restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai 2 hal, yaitu mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis di masa yang akan datang. Kebijakan khusus yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan, termasuk restrukturisasi peran dan tugas bank sentral. Dalam UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya BI 28 mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang perumusannya dilakukan oleh Dewan Moneter. Hal ini mencerminkan tidak adanya batas yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara BI dengan pemerintah, serta mencerminkan pula keterbatasan wewenang BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter dan perbankan. Kurang efektifnya langkah-langkah yang ditempuh oleh BI dalam mengatasi krisis 1997 ditengarai disebabkan oleh terbatasnya kewenangan. Untuk itu, diperlukan landasan hukum yang baru, yang memberikan status, tujuan, dan tugas yang sesuai kepada BI sebagai bank sentral (PPSK BI, 2003). Dengan tujuan agar BI lebih independen, pemerintah memberlakukan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Inti dari UU yang baru adalah bahwa kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah dan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Pengertian independensi menurut UU ini adalah BI bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan tugasnya4. Berdasarkan UU yang baru, tujuan utama yang hendak dicapai BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan di atas, BI melaksanakan tiga tugas pokok, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta (iii) mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara antara lain: (i) operasi pasar terbuka, (ii) penetapan tingkat diskonto, (iii) penetapan cadangan wajib minimum, dan (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan5. 4 5 Keseluruhan isi UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diakses dari http://www.bi.go. id/biweb/html/uu231999_id/uu.pdf pada 5 Desember 2011 Ibid 29 Pelaksanaan independensi BI memerlukan adanya koordinasi dengan lembaga lainnya, khususnya dengan otoritas fiskal. Independensi BI akan kurang efektif apabila tidak diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan fiskal yang juga bertanggung jawab, berdisiplin dan transparan. UU yang baru telah mengatur bentuk koordinasi antara BI dengan pemerintah, sebagai berikut (UU No. 23 Tahun 1999)6: 1. BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Atas permintaan pemerintah, BI untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 2. Pemerintah wajib meminta pendapat dan/atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas mengenai masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI. BI juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. 3. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI apabila akan menerbitkan surat utang negara. BI dapat membantu penerbitan surat utang negara terutama informasi mengenai pasar dan waktu penerbitan surat utang tersebut. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat utang negara tersebut di pasar primer dan hanya dapat membeli di pasar sekunder yang semata-mata hanya untuk tujuan pelaksanaan kebijakan moneter. 4. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah karena dianggap dapat mengganggu keutuhan konsep independensi BI. Sebelum UU yang baru, pemberian kredit kepada pemerintah ditujukan untuk memperkuat kas negara dalam mengatasi defisit pengeluaran pemerintah. 6 30 Ikhtisar Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diakses dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/13303/ikhtisar.pdf pada 5 Desember 2011 5. Walaupun BI merupakan lembaga yang independen, namun koordinasi dengan pemerintah yang bersifat konsultatif tetap diperlukan. Pemerintah yang diwakili seorang menteri atau lebih dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur dengan hak bicara tanpa hak suara. 6. Hubungan dengan pemerintah juga nampak dalam pembagian surplus dari hasil kegiatan BI. Sisa surplus BI setelah dikurangi 30% untuk cadangan tujuan dan 10% untuk cadangan umum diserahkan kepada pemerintah dengan ketentuan terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah kepada BI. Dalam perjalanannya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pokok dari amandemen tersebut adalah7: 1. Pembentukan Dewan Supervisi untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI. Pembentukan Badan Supervisi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Supervisi tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada DPR. 2. BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi meng- 7 Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diakses dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/20082/penj_uu_ri_3_2004.pdf pada 5 Desember 2011 31 akibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (Indonesia Financial Safety Net) yang akan diatur dalam undangundang tersendiri. 3. Berkaitan dengan penyusunan RAPBN, BI diwajibkan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar penyusunan RAPBN dapat mempertimbangkan lebih cermat aspek moneter yang terkait dengan berbagai kebijaksanaan di bidang fiskal. 4. Pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari BI Pengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi yang dimulai 1997 yang lalu menunjukkan bahwa meskipun koordinasi fiskal dan moneter penting, namun tidak berarti dapat dilakukan dengan mudah jika bank sentral independen dari pemerintah. Lemahnya koordinasi kebijakan bisa menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan ekonomi. Oleh karena itu perlu dijaga agar koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter dapat berjalan dengan baik, sehingga stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan baik, dan pembangunan ekonomi dapat berhasil mensejahterakan dan memajukan masyarakat. Namun demikian ternyata seiring dengan ekonomi yang semakin terbuka, dan juga pasar keuangan yang semakin terintegrasi pada tingkat global. Maka koordinasi fiskal dan moneter yang baik dalam pengelolaan ekonomi sudah tidak mencukupi lagi. Perlu koordinasi yang lebih luas untuk menjaga stabililtas ekonomi makro dan membangun ekonomi. 32 4. Periode Setelah Krisis Finansial Global Perbankan Indonesia yang sehat dan kuat setelah restrukturisasi sektor perbankan yang dilakukan sejak krisis 1997 menjadi modal besar bagi Indonesia dalam menghadapi krisis finansial global di tahun 2008. Sehingga pasar keuangan Indonesia dapat bertahan dengan cukup baik menghadapi krisis global tersebut. Selain itu berbagai kebijakan yang diambil oleh otoritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dapat membawa Indonesia dengan cukup baik melewati krisis global tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia sewaktu krisis tersebut berlangsung yang terkait dengan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal adalah (Adiningsih et.al., 2011): 1. 2. Kebijakan moneter a. BI rate diturunkan secara bertahap dari 8,75 persen pada awal semester I 2009 hingga 7 persen di akhir semester II 2009. Kemudian BI menghentikan pemotongan suku bunga, menjaganya tetap berada di kisaran 6,5 persen sejak Agustus 2009. b. BI melakukan kebijakan intervensi pasar valuta asing. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar, terutama pada saat ada faktor-faktor yang dapat berdampak negatif pada mata uang Indonesia. Namun, intervensi ini hanya dilakukan saat himbauan tidak efektif dalam mempengaruhi pasar. Jaminan atas Simpanan (Deposit Guarantees) Pemerintah menerbitkan dua peraturan pemerintah tentang jaminan simpanan di bank yang secara efektif meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. 3. Stimulus Fiskal Pemerintah menyediakan paket stimulus berjumlah total Rp 71,3 triliun pada tahun 2009. 33 Selain itu, sebagai upaya menanggulangi krisis finansial global 2008, pemerintah menerbitkan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU), yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU Pokok dari PERPPU ini adalah8: a. BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. b. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. c. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam undang-undang tersendiri. PERPPU ini kemudian ditetapkan menjadi UU yaitu UU no. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU 2. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi pencegahan dan penanganan krisis. Pencegahan krisis dilakukan melalui penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan masalah solvabilitas dari bank dan 8 34 Keseluruhan isi PERPPU No. 2 Tahun 2008 diakses dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/16333/Perpu_2_Tahun_2008.pdf pada 5 Desember 2011 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi bank atau bantuan likuiditas bagi LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas9. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Nilai simpanan yang dijamin LPS dapat diubah jika terjadi: 1) bank run; 2) inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; 3) pengurangan jumlah nasabah yang dijamin menjadi kurang dari 90% dari jumlah penyimpan seluruh bank; 4) ancaman krisis. Terkait dengan PERPPU ini, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa jumlah simpanan yang dijamin menjadi paling banyak Rp 2 miliar jika terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam PERPPU tersebut. Nilai simpanan yang dijamin semula adalah Rp 100 juta (Santoso, 2008). Beberapa pelajaran yang dapat ditarik dari krisis 2008 yang menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal semakin penting adalah (Adiningsih, 2010): 1. Besarnya nilai capital inflows yang ada di Indonesia, sehingga ada ancaman pembalikan capital inflows. Perkembangan pasar valuta asing perlu dicermati karena memiliki potensi volatilitas yang tinggi, seperti yang terjadi pada waktu krisis keuangan global 2008 yang lalu. 2. Pemberian stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis menyebabkan defisit APBN. Defisit APBN dibiayai dengan menerbitkan Surat Berharga Negara yang volumenya semakin besar. Padahal likuiditas pasar keuangan masih 9 Keseluruhan isi PERPPU No. 4 Tahun 2008 diakses dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/17685/Perpu4Tahun2008JaringPengamanSistKeu.pdf pada 5 Desember 2011 35 terbatas, khususnya dana domestik yang tersedia di pasar modal masih belum dapat memenuhi kebutuhan dana yang semakin meningkat, sehingga dapat menyebabkan terjadilah fenomena “crowding out”. Kondisi tersebut menuntut perlunya koordinasi fiskal dan moneter yang baik agar supaya stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) mencatat bahwa strategi yang paling efektif dalam menghadapi dampak krisis 2008 adalah koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter—dan regulator keuangan. Bank sentral dan Kementerian Keuangan harus selalu bekerja sama agar tidak mengambil kebijakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat (Kuroda, 2010). Koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diperlukan dalam perekonomian global seperti saat ini semakin penting dan kompleks, perlu diperluas, seperti yang disampaikan oleh ADB. Isu-isu penting yang perlu dibahas dalam pelaksanaan koordinasi tersebut ada banyak, di antaranya adalah (Adiningsih, 2010): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Koordinasi dalam aktivitas keuangan Komunikasi dalam kebijakan Central bankers “lean against the wind” Formal fiscal rules? Transparansi dalam kebijakan fiskal dan moneter Koordinasi dalam mengelola atau mengawasi atau mengontrol short term capital inflows Koordinasi dalam Macroprudential Koordinasi dalam Microprudential Dimana dalam pasar keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan terintegrasi secara global seperti sekarang ini berbagai isu tersebut perlu dicari solusinya. Koordinasi tidak lagi cukup untuk kebijakan fiskal dan moneter, namun juga otoritas keuangan lainnya, bahkan juga perlu pengawasan selain aspek resiko keuangan secara mikro, juga secara makro. 36 Untuk menjaga stabilitas keuangan, koordinasi antar otoritas keuangan sangat diperlukan. Saat krisis 2008, Menteri Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan menandatangani perjanjian kerja sama yang tujuannya adalah membangun dasar yang kuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi perekonomian dari kemungkinan terjadinya krisis di masa mendatang. Dalam MoU tersebut, otoritas keuangan yang terlibat setuju untuk saling membagi informasi mengenai kondisi sektor keuangan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Mereka juga bersepakat untuk membuat sebuah protokol manajemen krisis. Oleh karena itu diperlukan suatu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai antisipasi krisis di masa mendatang. JPSK merupakan mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (Adiningsih, et.al., 2011). Setelah batal disahkan disahkan DPR pada periode 2004-2009, pemerintah berniat untuk mengusulkan kembali RUU tentang JPSK. Dalam RUU ini, dimuat secara jelas tugas dan tanggung jawab lembaga terkait yaitu Kementerian Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam jaring pengaman keuangan. Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. LPS bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah. UU JPSK jika jadi diundangkan, kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan. Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif. 37 Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, di tahun 2003, Indonesia mengambil langkah awal dalam supervisi makro prudensial dengan mendirikan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) . FSSK mengembangkan Early Warning System (EWS) yang disebut Financial Stability Index (FSI) dengan tujuan mendeteksi vulnerabilitas sektor perbankan. Maka, ketika krisis 2008 meluas, pemerintah Indonesia dapat merespon dengan cepat karena indeks stabilitas keuangan pada November 2008 tercatat sebesar 2,43; di atas indikasi maksimum sebesar 2,0 (Bank Indonesia, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia dan sistem keuangan domestik berada dalam kondisi kritis. Salah satu kebijakan yang kemudian disetujui oleh BI adalah mengurangi batas minimal cadangan minimum bank di bank sentral dari 9,08% menjadi 7,5% seperti tercantum dalam PBI No. 10/19/PBI/2008 bertanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum bagi bank komersial. Hal ini merupakan langkah antisipasi dari BI. Jika otoritas ekonomi harus menunggu hingga bank terkena dampak krisis, reaksi pemerintah akan menjadi terlambat. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengembangkan EWS yang memonitor beberapa indikator kunci, seperti IHSG, nilai tukar rupiah, pertumbuhan GDP, penjualan bersih saham dan obligasi dalam Bursa Saham Indonesia, serta nilai ekspor dan impor. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai simulasi sehingga dampaknya bagi APBN dapat diprediksi (Adiningsih, et.al., 2011). Selain itu, dengan tujuan mereformasi sektor keuangan, Indonesia pada akhirnya mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring dengan disahkannya undang-undang tentang OJK oleh Presiden pada tanggal 22 November 2011. Dengan disahkannya UU OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang selama ini dilakukan Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) akan beralih ke OJK. Sementara untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh BI akan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013. Di dalam UU ini telah dicantumkan mengenai protolol koordinasi di antara otoritas 38 keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) dengan Menteri Keuangan sebagai anggota merangkap koordinator serta anggota lainnya adalah Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Bahkan FKSSK juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk pencegahan ataupun menangani krisis. OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan begitu, BI tak lagi mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Undang-undang OJK, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia (penjelasan pasal 7 Undang-undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan. OJK yang merupakan lembaga yang independen, dengan sembilan anggota dewan komisaris yang sifatnya kolektif kolegial. Selain itu, akan ada dua anggota unsur perwakilan ex-officio dari perwakilan BI dan Kementerian Keuangan. Perwakilan ex-officio dibutuhkan untuk menjalin koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara OJK, otoritas fiskal, dan otoritas moneter. Dengan demikian diharapkan koordinasi antara OJK, BI dan Kementrian Keuangan dapat berjalan dengan baik. Penutup Koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya antara fiskal dan moneter semakin penting. Namun sejarah menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan 39 fiskal dan moneter yang baik saja tidaklah cukup, meskipun diperlukan. Kebijakan fiskal yang pruden serta kebijakan moneter bertanggung jawab, yang dibarengi dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang baik, disertai dengan pertanggung jawaban yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal akan membantu terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pembangunan ekonomi. Namun demikian kondisi pasar keuangan dunia yang berkembang pesat dan banyak memunculkan produk-produk keuangan canggih serta semakin terintegrasi pasar keuangan global menyebabkan resiko yang dihadapi dalam sistem keuangan juga semakin besar, volatilitas semakin tinggi dan pasar juga semakin dinamis. Berkaca dari pengalaman krisis moneter 1997 dan krisis finansial global 2008 serta krisis yang menimpa zona Euro di tahun 2010, terlihat jelas bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berperan penting sebagai langkah antisipasi krisis ataupun mengatasi krisis keuangan. Lebih lanjut, diperlukan koordinasi yang lebih luas tidak hanya kebijakan moneter dan fiskal tapi juga dengan otoritas keuangan lainnya (seperti OJK dan LPS) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Demikian juga diperlukan koordinasi kebijakan makroprudensial yang baik, agar dapat menjaga stabilitas ekonomi makro dengan lebih baik dan pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi berkelanjutan. 40 Referensi Adiningsih, S. 2010. Koordinasi Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Kestabilan Ekonomi Makro di Indonesia. Disampaikan dalam Fokus Group Discussion “Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Kestabilan Ekonomi Makro di Indonesia” yang diselenggarakan atas kerja sama ISEI Fokus Group Koordinasi Fiksal dan Moneter dengan Bank Indonesia – Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. 19 November 2010. Jakarta. Adiningsih, Ssenyonga, Rahutami, Devi, dan Kristiadi. 2011. Contributing to Efforts for Greater Financial Markets Stability in APEC Economies. APEC Study. APEC Finance Minister Process. Asian Development Bank. 2011. Government Finance: Tax Revenue. Asian Development Bank. Bank Indonesia. 2007a. Sejarah Bank Indonesia: Kelembagaan Periode 1953 – 1959. Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia. https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bi.go. id%2FNR%2Frdonlyres%2FCF79E6F1-376E-45E5-ADCD-17B9D59587B0%2F865%2FSejarahMoneterPeriode19531959.pdf Bank Indonesia. 2007b. Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 19831997. Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/CF79E6F1-376E-45E5-ADCD-17B9D59587B0/868/SejarahMoneterPeriode19831997.pdf Bank Indonesia. 2009. Financial Stability Review. No 13 September 2009. Bank Indonesia. Jakarta. Boediono. 2001. Ekonomi Makro. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta. Corsetti, G. dan Mueller, G. 2008. What Makes Fiscal Policy (More) Effective? http://www.economonitor.com/blog/2008/11/what-makes-fiscal-policymore-effective/ 41 Hanif, M. N. dan Arby, M. F. 2003. Monetary and Fiscal Policy Coordination. MPRA Paper No. 10307. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10307/1/MPRA_paper_10307. pdf Kuroda, H. 2010. Recovery and Beyond: Policy Challenges and the Future of Asian Integration. Opening remarks at the 16th International Conference on the Future of Asia toward an Open Economic Partnership, Tokyo, Japan. Asian Development Bank. http://beta.adb.org/ news/speeches/recovery-and-beyond-policy-challenges-and-futureasian-integration Nopirin. 1996. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro. BPFE. Yogyakarta. Prawiro, R. 1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi. Elex Media Komputindo. Jakarta. PPSK BI. 2003. Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi. Bank Indonesia. Jakarta. Sabirin, S. 2000. Upaya Pemulihan Ekonomi Melalui Strategi Kebijakan Moneter – Perbankan dan Independensi Bank Indonesia. www.bi.go. id/NR/rdonlyres/4F64F9EB-CAF1.../gubfeb022000.pdf. Santoso, W. 2008. Langkah dan Kebijakan Bank Indonesia Menghadapi Krisis Keuangan Global. Disampaikan dalam Seminar Stabilitas Keuangan: Menghadapi Tantangan dari Dampak Potensial Krisis Keuangan di Solo, 16-18 Desember 2008. Tarmidi, L.T. 1999. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Maret. 42 KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL: TANTANGAN DAN STRATEGI PEMELIHARAAN STABILITAS MAKRO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Miranda Swaray Goeltom Pendahuluan Secara teoritis maupun empiris, kebijakan moneter dan fiskal mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka stabilisasi perekonomian, yaitu melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila perekonomian mengalami tekanan inflasi yang cukup besar, misalnya, maka kebijakan stabilisasi diarahkan pada pengurangan permintaan agregat. Sebaliknya, pada saat ekonomi mengalami resesi maka kebijakan stabilisasi lebih diarahkan untuk menstimulasi permintaan agregat. Walaupun kebijakan moneter dan fiskal berdampak pada struktur dan kondisi ekonomi yang berlainan, keduanya dapat digunakan secara simultan untuk mencapai dua sasaran stabilitas yang berlainan, misalnya pencapaian keseimbangan internal (stabilitas harga) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran). Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter dan fiskal dapat dikelola atau dikoordinasikan sedemikian rupa agar stimulus yang dihasilkan oleh kedua kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mempengaruhi perekonomian, dalam artian tidak saling meniadakan atau bahkan menimbulkan pengaruh yang berlebihan, sehingga dapat mendukung pencapaian stabilitas harga dan pencapaian neraca pembayaran yang sehat secara bersama-sama. 43 Dalam tataran praktis, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi semakin penting manakala terdapat ketidak pastian yang tinggi dari pengaruh masing-masing kebijakan (Blinder, 1982). Pentingnya koordinasi kebijakan dalam situasi ini dicontohkan dalam kasus di banyak negara maju dan emerging countries pada awal tahun 2000-an ketika perekonomian dunia menunjukkan kelesuan yang berlarut, dimana terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi dari pengaruh kebijakan yang telah diambil, sementara dari sisi moneter tingkat suku bunga sudah ditekan sedemikian rendahnya. Kebijakan yang dilakukan secara parsial dan bertahap cenderung akan semakin meningkatkan ketidakpastian dan resiko, yang dapat mendorong penurunan kinerja perekonomian lebih lanjut. Untuk itu, banyak ahli ekonomi yang menyarankan strategi yang sebaiknya ditempuh adalah koordinasi kebijakan dan penggunaan berbagai instrumen kebijakan secara lebih agresif untuk mendukung efektivitas kebijakan yang diambil (Mohanty and Scatigna, 2004). Walaupun koordinasi kebijakan diyakini akan memberikan hasil yang lebih baik untuk perekonomian, dalam praktek masih banyak dijumpai kurangnya koordinasi kebijakan. Di banyak negara, kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sering menjadi permasalahan dalam perumusan dan penerapan kebijakan perekonomian, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat pada awal 1980-an. Saat itu, kebijakan fiskal yang diambil cenderung ekspansif untuk mengatasi kelesuan ekonomi akibat krisis energi yang terjadi sejak awal tahun 1970-an, sementara pada saat yang bersamaan, tekanan inflasi yang terus menguat hingga 13,5% pada tahun 1980 direspons dengan kebijakan moneter kontraktif, dimana suku bunga (prime rate) terus meningkat hingga mencapai 20% pada pertengahan 1981. Sebagai akibatnya resesi ekonomi yang dialami berkepanjangan hingga beberapa tahun kemudian. Menarik untuk mengamati berbagai tulisan yang terkait dengan kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal (antara lain Blinder, 1982; Dodge, 2002), yang pada intinya mengemukakan tiga faktor mendasar penyebab terjadinya hal tersebut. Pertama, otoritas moneter 44 dan fiskal umumnya mempunyai tujuan kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena mandat dan konstitusi yang berbeda, ataupun karena pandangan yang berbeda terhadap cara terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, otoritas moneter dan fiskal mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi perekonomian. Sebagai contoh, pemerintah memandang bahwa pemotongan pajak dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan tanpa berdampak buruk terhadap investasi. Sementara itu, otoritas moneter mungkin memandang pemotongan pajak tersebut dapat mengakibatkan peningkatan defisit anggaran sehingga terjadi crowding out investasi swasta. Ketiga, otoritas moneter dan fiskal mempunyai prediksi yang berbeda mengenai kondisi (state) perekonomian. Kemungkinan perbedaan prediksi dapat terjadi karena adanya perbedaan landasan teori ekonomi maupun variabel-variabel prakiraan (forecasting) yang digunakan. Gambaran di atas mencerminkan sulitnya merumuskan bentuk koordinasi yang universal untuk dapat diterapkan di semua negara. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam periode lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi bagian penting dalam pasang surut perjalanan perekonomian bangsa ini. Pada periode hingga pertengahan tahun 1990an, permasalahan koordinasi belum begitu menggema manakala kebijakan moneter berada di bawah pengaturan Dewan Moneter, yang diketuai oleh Menteri Keuangan (sebagai wakil pemerintah) dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri perekonomian. Pada masa itu orientasi stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan dalam dimensi Trilogi Pembangunan ditetapkan sebagai jangkar kebijakan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan legitimasi politik pada masa itu, bentuk koordinasi satu atap tersebut cukup berperan dalam meningkatkan derajat kepastian arah kebijakan ekonomi. Namun, di sisi lain, pengalaman juga menunjukkan kecenderungan munculnya dilema dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dalam kapasitasnya 45 sebagai otoritas moneter dan perbankan tidak selalu dapat menetapkan kebijakan moneter yang dianggapnya tepat karena perbedaan prioritas dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, keinginan otoritas moneter meningkatkan suku bunga untuk meredam inflasi tidak dapat dilakukan jika Dewan Moneter menganggap kebijakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Contoh lainnya, meskipun hasil pengawasan Bank Indonesia menyimpulkan adanya beberapa bank yang harus ditutup, hal tersebut tidak dapat dilakukan manakala Dewan Moneter menganggap penutupan tersebut belum perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan tertentu. Belajar dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1997/98, Pemerintah Indonesia menggulirkan reformasi politik dan ekonomi yang antara lain merubah UU No. 13 Tahun 1968 dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diamandemen oleh UU No. 3 Tahun 2004. Dengan landasan hukum yang baru tersebut tujuan Bank Indonesia menjadi lebih terfokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Secara kelembagaan, Bank Indonesia diberikan independensi dalam penggunaan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, sasaran inflasi yang akan dicapai oleh kebijakan moneter ditetapkan oleh pemerintah, dengan berkoordinasi bersama Bank Indonesia. Landasan hukum yang baru tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Penerapan kerangka kerja dengan tujuan tunggal memelihara kestabilan nilai rupiah mengharuskan Bank Indonesia menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan target inflasi tertentu. Sementara itu, amanah independensi menuntut adanya standar pencapaian kinerja kelembagaan yang memadai dalam bentuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi kebijakan. Namun demikian, penafsiran dan implementasi kebijakan tujuan tunggal di atas harus dikaitkan dengan berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi dewasa ini. Pertama, terjadinya perubahan pola hubungan antar variabel ekonomi makro akibat pengaruh 46 sektor eksternal yang semakin kuat, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kondisi ini diperberat dengan adanya kecenderungan ketidakseimbangan sektoral, dimana perkembangan yang pesat di sektor keuangan belum diimbangi dengan respons sektor riil yang memadai (’decoupling’). Kedua, masih terdapatnya kekakuan struktural (structural rigidity) dimana sisi penawaran kurang responsif terhadap stimulus sisi permintaan, sehingga pertumbuhan yang realtif tinggi belum dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan (paradox of growth). Ketiga, dengan adanya otonomi daerah, tugas otoritas moneter dalam menjaga target inflasi menjadi lebih berat karena sumber inflasi menjadi lebih meyebar dan lebih sulit dikontrol. Dan keempat, dinamika politik dalam negeri yang sedang menuju pendewasaan terkadang cenderung kurang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi. Persepsi ini muncul sejalan dengan euforia demokrasi dalam jangka pendek yang cenderung berdampak kurang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi (Boediono, 2007). Gambaran di atas menunjukkan, paling tidak, terdapat dua isu koordinasi yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan mempertimbangkan fakta bahwa pada periode pascakrisis hingga saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam tahap pengupayaan pemulihan dan penguatan kondisi perekonomian secara makro, muncul pemikiran yang cukup relevan, mengenai perlu atau tidaknya bank sentral dibebani pula tugas untuk memelihara pertumbuhan ekonomi pada kondisi kesempatan kerja penuh bersama-sama tugas untuk mencapai laju inflasi yang rendah. Kedua, dengan skala independensi yang telah diamanahkan, yang disertai dengan lingkungan ketidakpastian yang masih menyelimuti dinamika perekonomian baik nasional maupun global, koordinasi kebijakan perlu dirumuskan dan diletakkan dalam tataran yang sangat strategis. Dengan memperhitungkan dinamika ekonomi seperti diuraikan di atas, pokok pemikiran yang akan disampaikan dalam tulisan ini akan mengacu pada beberapa pertanyaan mendasar dalam perumusan strategi kordinasi kebijakan moneter dan fiskal, yaitu: Pertama, sejauh mana 47 pelaksanaan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia saat ini, serta permasalahan apa yang muncul? Kedua, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana strategi koordinasi yang perlu dirumuskan agar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat diarahkan pada upaya untuk memelihara stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi secara efektif? Terakhir, bagaimana koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diletakkan dalam tataran yang lebih strategis, yaitu dalam perumusan semacam contigency plan atau format tertentu untuk merespons kejutan struktural (shocks) dan ketidak pastian yang mungkin muncul? Dimensi Konseptual dan Studi Empiris di Beberapa Negara Pentingnya Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Perdebatan mengenai pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari adanya perbedaan penekanan dalam peran dan pencapaian tujuan masing-masing kebijakan, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan. Perbedaan penekanan tujuan tersebut dapat mengakibatkan hasil dari masing-masing kebijakan menjadi tidak optimal atau bahkan saling meniadakan (set-off). Oleh karena itu, kedua otoritas perlu menerapkan strategi bauran kebijakan (policy mix) yang optimal dalam rangka mencapai stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 1990-an, tujuan kebijakan moneter lebih difokuskan pada stabilitas harga dengan beberapa pertimbangan. Pertama, segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (aggregate demand) dalam jangka pendek akan menciptakan inflasi (the short-run Phillip Curve) sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil dalam jangka panjang (Kydland and Prescott, 1977). Kedua, rational economic agent memahami bahwa shocks pembuat kebijakan dalam mendorong inflasi dapat menimbulkan permasalahan time-inconsistency (Barro and Gordon, 1983). Ketiga, kebijakan moneter mempunyai tenggat waktu (time lag) dalam mempengaruhi variabel ekonomi, sehingga menuntut kebijakan moneter yang forward looking (Friedman, 1968). Keempat, kestabilan 48 harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena mengurangi ekspektasi inflasi. Keempat pertimbangan di atas mencerminkan bahwa penetapan stabilitas harga akan mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain pencapaian kebijakan moneter yang tidak dilakukan secara terukur juga dapat mengakibatkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan moneter yang terlalu ketat (tight) dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu longgar (loose) dapat menimbulkan tekanan inflasi yang mengganggu daya beli masyarakat dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dnegan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya defisit fiskal yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Traclet (2004) menunjukkan berbagai dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah yang tidak terkendali, antara lain: Pertama, defisit fiskal dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang pemerintah dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah obligasi pemerintah yang dikeluarkan untuk menutup defisit fiskal dapat menciptakan crowdingout effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, defisit fiskal yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Pengalaman empiris negara-negara di Amerika Latin pada akhir tahun 1980-an menunjukkan bahwa pembiayaan defisit fiskal yang besar dan terjadi terus-menerus melalui penciptaan uang baru oleh bank sentral telah mengakibatkan hiper inflasi dan resesi ekonomi yang dalam. Pada periode tahun 1988-1991, defisit fiskal pemerintah Peru telah mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1.052,6% per tahun. Pesatnya pertumbuhan uang beredar tersebut tanpa diikuti peningkatan produksi merupakan penyebab melesatnya laju inflasi di negara tersebut hingga 49 mencapai 1.694,3%. Hiper inflasi tersebut telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga Peru mengalami resesi ekonomi yang dalam. Pengalaman negara-negara Afrika, beberapa negara Eropa dan negara-negara Amerika Latin lainnya juga menggambarkan pola yang sama, yaitu defisit fiskal yang berlebihan yang mengakibatkan tingginya uang beredar dan hiper inflasi. Beberapa data empiris tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang longgar dengan kebijakan moneter yang longgar melalui penciptaan uang baru untuk pembiayaan defisit dapat mengakibatkan terjadinya hiper inflasi dan gangguan stabilitas ekonomi makro. Uraian di atas kembali mencerminkan perlunya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Oleh sebab itu menarik untuk menelaah bagaimana hasil bauran kebijakan (policy mix) dari kedua otoritas tersebut. Secara teoritis, terdapat 4 pilihan bauran kebijakan moneter dan fiskal, yaitu: (i) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar; (ii) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat; (iii) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar; dan (iv) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat. Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu: kebijakan ketat maupun kebijakan longgar (a tight or a loose policy). Ketika keduanya bersama-sama memilih kebijakan pengetatan maka tingkat inflasi cenderung rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi), sedangkan ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang longgar maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka pengangguran cenderung rendah. Sementara itu, apabila salah satu otoritas kebijakan membuat kebijakan pengetatan sedangkan yang lain membuat kebijakan pelonggaran atau sebaliknya, maka tingkat pengangguran dan inflasi cenderung berada pada tingkat sedang. Nash Equilibrium1 pada interaksi ini adalah bauran kebijakan moneter 1 50 Nash equilibrium adalah tingkat keseimbangan yang memberikan hasil terbaik dengan memperhitungkan respon optimal masing-masing pelaku (agent), seperti diperkenalkan oleh John Nash pada tahun 1950. ketat dan kebijakan fiskal longgar, atau bauran kebijakan moneter longgar dan kebijakan fiskal ketat. Nilai hasil bauran (payoff) untuk kebijakan moneter ketat dan kebijakan fiskal longgar sama dengan nilai payoff untuk kebijakan moneter longgar dan kebijakan fiskal ketat. Namun dari studi empiris Bennett dan Loayza (2002) yang membandingkan berbagai negara terlihat bahwa dalam jangka panjang, kombinasi kebijakan moneter longgar dan fiskal ketat lebih sehat daripada kebijakan moneter ketat dan fiskal longgar. Hal ini disebabkan kebijakan moneter longgar dan fiskal ketat tidak berkompromi terhadap fiscal sustainability dan tidak memperlemah kapasitas investasi sektor swasta (crowding-out effect). Hasil kajian yang dilakukan Petit (1989) di Italia, Javed dan Sahinoz (2005) di Turki dan penelitian lainnya di berbagai negara menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi makro suatu negara. Untuk kasus Indonesia, penelitian yang dilakukan Goeltom dan Simorangkir (2005) dengan menggunakan model game theory menunjukkan bahwa cooperative game antara kebijakan moneter dan fiskal memberikan hasil kerugian terkecil (minimum loss) dibandingkan dengan non-cooperative game seperti akan diuraikan pada bagian lain. Dalam prakteknya, terdapat pilihan model koordinasi moneterfiskal, seperti dikemukakan Blinder (1982), dimana masing-masing model koordinasi tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. (i) Kebijakan Moneter dan Fiskal berada dalam ”Satu Atap” Dengan koordinasi seperti ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ditentukan oleh satu institusi yang membawahi baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal. Koordinasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik apabila objektif dan metode yang digunakan untuk mencapai objektif tersebut mempunyai ketidakpastian yang kecil. (ii) Dua otoritas kebijakan yang independen Dalam model ini masing-masing otoritas fiskal dan otoritas moneter mengambil kebijakan secara independen, tanpa adanya dominasi satu otoritas terhadap otoritas lainnya. Sebagai contoh, karena tekanan 51 terhadap anggaran pemerintah yang semakin berat, otoritas fiskal mengurangi subsidi atau meningkatkan pajak. Di sisi lain karena tekanan terhadap inflasi yang besar otoritas moneter mengambil kebijakan moneter yang ketat. Dengan menggunakan pendekatan game theory, Blinder menunjukkan bahwa tanpa koordinasi akan diperoleh Nash equilibrium yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan adanya koordinasi. Hasil ini didasarkan pada asumsi bahwa otoritas fiskal dan moneter saling mengetahui preferensinya. (i) Leader-Follower Dengan sistem ini, salah satu otoritas akan mengambil suatu kebijakan sedangkan otoritas yang lain akan menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh otoritas yang bergerak pertama. Sebagai contoh, otoritas fiskal terlebih dahulu mengambil kebijakan mengenai defisit anggaran dan kemudian diikuti oleh kebijakan moneter didasarkan pada kebijakan fiskal yang telah diambil. Ataupun sebaliknya, otoritas moneter mengambil kebijakan moneter terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh kebijakan fiskal didasarkan pada kebijakan moneter yang telah diambil. Dengan sistem leader-follower, keputusan yang diambil oleh leader tentu saja mempertimbangkan respon yang akan diambil oleh follower. Sebagai contoh, apabila otoritas fiskal bertindak sebagai leader tentu saja akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang ekspansif, karena otoritas moneter akan meningkatkan suku bunga apabila kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut dianggap memberikan tekanan yang cukup besar terhadap inflasi. Kebijakan Moneter dalam ITF dan Pentingnya Koordinasi Kebijakan Terdapat konsensus yang terus berkembang belakangan ini mengenai peran relatif antara kebijakan moneter dan fiskal serta pentingnya dilakukan kebijakan terpadu moneter-fiskal (monetary-fiscal policy mix). Kecenderungan yang terjadi dewasa ini adalah penggunaan rules-based 52 frameworks. Dalam kebijakan fiskal dikenal adanya fiscal policy rule, misalnya melalui disiplin anggaran dengan penetapan persentase defisit anggaran tertentu dan dalam kebijakan moneter terdapat kecenderungan penerapan inflation targeting framework (ITF). Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, semakin terintegrasinya sistem keuangan dunia telah menyebabkan penggunaan besaran moneter (monetary aggregates) semakin kurang dapat diandalkan sebagai target untuk mengendalikan inflasi. Pertumbuhan besaran moneter yang cepat seringkali dianggap merupakan refleksi telah terjadinya financial deepening daripada sebagai suatu ancaman inflasi. Oleh karena itu, penggunaan inflation targeting framework (ITF) semakin banyak diadopsi oleh negaranegara berkembang karena mereka menyadari bahwa kebijakan moneter yang tepat menuntut otoritas moneter untuk mempunyai komitmen yang jelas terhadap pencapaian inflasi yang rendah. Knight (2007) menyatakan bahwa terdapat paling sedikit tiga keuntungan menggunakan target inflasi yang eksplisit sebagai kerangka kebijakan moneter. Pertama, ITF memperbaiki transparansi yang mengarah kepada komunikasi yang lebih baik sehingga dapat membantu publik memahami tujuan (goals) dari bank sentral. Pada gilirannya, pemahaman publik yang semakin baik akan membantu membuat kebijakan moneter semakin kredibel dan dengan demikian dapat menjadi jangkar (anchor) ekspektasi inflasi. Upaya-upaya memberikan transparansi dilakukan melalui laporan kepada publik secara reguler mengenai prakiraan inflasi dan pertimbangan-pertimbangan di balik keputusan kebijakan moneter yang diambil. Kedua, sifat forward-looking ITF mendorong otoritas moneter untuk fokus pada inflasi di masa depan (future inflation). Dengan fokus pada inflasi di masa depan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengurangi (smoothing) dampak dari shocks agar mengarah kepada resesi yang lebih pendek dan dangkal pada saat permintaan domestik melemah. Sepanjang ekpektasi inflasi tetap terjaga dengan baik (well anchored) pada suatu target inflasi tertentu, shocks yang bersifat sementara yang memiliki dampak jangka pendek yang besar pada inflasi, tidak perlu direspon dengan 53 kebijakan moneter yang berlebihan. Ketiga, ITF membuat bank sentral lebih transparan dan akuntabel. Karena ITF menuntut transparansi, publik dapat dengan mudah melihat apakah bank sentral mencapai targetnya atau tidak. Akuntabilitas sangat penting bagi penerimaan publik terhadap independensi sebuah bank sentral dalam menetapkan instrumen kebijakan moneternya secara kredibel. Meskipun memiliki banyak keuntungan, ITF bukanlah obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala penyakit ekonomi. ITF harus didukung oleh kebijakan-kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Persyaratan pertama adalah tidak adanya pembiayaan secara langsung dari bank sentral kepada pemerintah untuk menutupi defisit fiskal. Monetisasi defisit fiskal yang besar, cepat atau lambat pasti akan menyebabkan inflasi yang semakin tinggi. Persyaratan kedua, kebijakan fiskal harus dijaga tetap berkelanjutan dengan menjaga besaran defisit fiskal yang tepat. Meskipun persyaratan pertama dipenuhi, misalnya dengan memiliki bank sentral yang independen, tetapi apabila persyaratan kedua dibiarkan relatif longgar maka dampak ekspansi kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat dan inflasi dalam perekonomian dapat memaksa bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi kredit dalam sistem keuangan. Tingginya tingkat suku bunga dapat menekan aktivitas ekonomi dan mengundang aliran modal jangka pendek masuk (short term capital inflow) yang rentan terhadap terjadinya pembalikan (capital reversal), sehingga menambah tekanan terhadap inflasi dan pada akhirnya mengganggu kestabilan makroekonomi dan keuangan. Salah satu studi teoritis yang mempelajari peran kebijakan fiskal sebagai sebuah instrumen stabilisasi makroekonomi di bawah kebijakan moneter dengan ITF adalah yang dilakukan oleh Roisland dan Torvik (2000). Dalam studi ini mereka mengasumsikan bahwa perekonomian dibagi ke dalam dua sektor yaitu traded sector2 dan non-traded sector. Secara umum, mereka menyimpulkan bahwa penggunaan dua instrumen (moneter dan fiskal) secara terkoordinasi adalah lebih baik daripada satu 2 54 Traded Sector adalah sektor ekonomi yang output nya diperdagangkan secara internasional. instrumen ketika dihadapkan pada pilihan antara menstabilkan inflasi atau mendorong perekonomian riil. Dalam perekonomian kecil terbuka, ITF dapat menghasilkan ketidakseimbangan (imbalances) antara sektor traded dan non-traded apabila kebijakan fiskal pasif. Dengan menyesuaikan posisi (stance) kebijakan fiskal untuk merespon berbagai shocks yang terjadi, maka kebijakan fiskal aktif dapat memberikan keseimbangan sektoral yang lebih baik, paling tidak apabaila terjadi kejutan yang berasal dari sisi permintaaan (demand shocks). Namun demikian, apabila terjadi kejutan dari sisi penawaran (supply shocks) pilihan-pilihan kebijakannya menjadi lebih sulit karena cenderung terjadi konflik antara pencapaian stabilitas sektor traded dan non-traded. Di bawah ITF, kebijakan fiskal tradisional yang counter-cyclical akan lebih besar pengaruhnya dalam mendestabilisasi (mengguncang) sektor traded daripada kebijakan fiskal pasif. Dengan demikian apabila terjadi supply shocks yang merugikan, maka untuk menjaga stabilitas di sektor traded, kebijakan fiskal seharusnya menjadi lebih ketat. Secara teoritis berdasarkan studi ini, kebijakan fiskal aktif di bawah ITF secara potensial dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang tinggi (large welfare gain), khususnya apabila stabilitas sektoral dapat terjaga dengan baik. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan ini tergantung dari biaya sosial yang timbul akibat dari penyesuaian stance kebijakan fiskal yang dilakukan untuk merespon kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dari studi Knight ini diperoleh nilai-nilai parameter yang menghasilkan biaya sosial yang relatif moderat sehubungan dengan penyesuaian kebijakan fiskal. Dengan biaya sosial yang relatif moderat ini, kebijakan fiskal seharusnya diterapkan dengan tidak terlalu aktif. Namun, karena adanya fakta bahwa efektivitas kebijakan fiskal cenderung berkurang di bawah ITF, maka dalam rangka mencapai social welfare gain yang tinggi, penyesuaian kebijakan fiskal harus dilakukan secara lebih aktif, meskipun dengan biaya sosial yang relatif moderat. Dengan demikian, perbedaan dalam social welfare gain antara memiliki kebijakan fiskal yang optimal (aktif ) dan memiliki kebijakan fiskal yang netral (pasif ) dapat menurun dengan cepat seiring dengan penyesuaian kebijakan fiskal yang aktif dilakukan. 55 Determinan Politik dalam Koordinasi Kebijakan Studi-studi mengenai hubungan antara interaksi fiskal-moneter dan politik—baik dilihat dari sisi ideologi maupun dari sisi pembagian kekuasaan—juga telah dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Sakamoto (2007), dengan menggunakan sampel negara-negara industri, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling berespons satu sama lain dan tergantung pada ideologi politik yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Di antara temuannya adalah bahwa pemerintah yang lebih liberal cenderung menggunakan kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dengan kebijakan moneter yang longgar. Temuan lainnya adalah bank sentral yang independen akan merespon kebijakan fiskal yang longgar yang dilakukan pemerintahan yang cenderung konservatif dengan mengetatkan kebijakan moneternya. Akhir-akhir ini berkembang studi yang mencoba menganalisa bagaimana interaksi fiskal-moneter pada saat kebijakan fiskal terdesentralisasi. Sejauh ini studi-studi tersebut fokus pada European Union, dimana kebijakan moneternya tersentralisasi dalam EMU sementara otoritas kebijakan fiskal dipegang oleh masing-masing negara anggota. Sebagaimana diungkapkan oleh Andersen (2005), dalam konteks EMU, masalah koordinasi muncul melalui dua jalur: (i) perubahan kebijakan fiskal di suatu negara dapat mempunyai efek terhadap inflasi di negara lain karena respons dari kebijakan moneter terhadap kebijakan fiskal tersebut; dan (ii) ekspansi fiskal domestik dapat memberikan manfaat bagi negara partner dagang melalui peningkatan permintaan terhadap barang impor. Untuk konteks Indonesia, kasus di EU tentu saja tidak sepenuhnya relevan karena perbedaan sistem moneter dan fiskal yang dianut. Namun demikian, otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal tentu saja membawa implikasi terhadap pengendalian moneter. Sebagai contoh, Treisman (1998) melakukan cross-country study, sementara itu Brodjonegoro et al. (2003) melihat bagaimana dampak pendapatan asli daerah dan belanja rutin terhadap inflasi di Indonesia. 56 Menurut Treisman (1998), terdapat dua pandangan yang berlawanan terhadap implikasi dari desentralisasi terhadap pengendalian inflasi. Kedua pandangan tersebut masing-masing mempunyai argumen dan contoh empiris. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi menurunkan inflasi karena dengan lebih menyebarnya kebijakan pengeluaran pemerintah, maka otoritas moneter dapat menjalankan komitmen yang lebih besar terhadap pengendalian inflasi. Pengalaman Jerman dan Swiss merupakan contoh yang dapat dijadikan pendukung pandangan ini dimana kuatnya pemerintah daerah di kedua negara tersebut dipandang telah membantu pemerintah pusat untuk lebih disiplin dan memelihara independensi bank sentral. Pandangan sebaliknya menyatakan bahwa desentralisasi dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi karena desentralisasi akan lebih menyulitkan koordinasi dalam menurunkan inflasi. Dengan desentralisasi yang lebih besar, baik dari sisi politik maupun dari sisi fiskal, maka pihak yang diperlukan untuk melakukan koordinasi dalam kebijakan stabilisasi akan semakin banyak. Pengalaman negara-negara Amerika Latin adalah contoh yang mendukung pandangan ini. Di berbagai negara Amerika Latin, desentralisasi politik telah meningkatkan tekanan untuk memperbesar pengeluaran pemerintah dan mendorong peningkatan pinjaman pemerintah yang berlebihan yang pada gilirannya menyulitkan kebijakan stabilisasi harga. Untuk kasus Indonesia, Brodjonegoro et al. (2003) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja rutin termasuk di antara faktor yang mempengaruhi inflasi. Pertumbuhan PAD yang terlalu ekspansif dalam era otonomi daerah dapat memicu inflasi melalui biaya melakukan usaha (cost of doing business) yang semakin tinggi sejalan dengan naiknya pungutan-pungutan untuk meningkatkan PAD. Sementara itu, belanja rutin yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi melalui peningkatan permintaan agregat sejalan dengan peningkatan belanja rutin. Dalam studi lain yang dilakukan oleh PPSK-BI bekerja sama dengan InterCAFE-IPB (2006) ditunjukkan juga bahwa desentralisasi 57 telah mendorong permintaan agregat baik melalui peningkatan konsumsi maupun investasi. Temuan-temuan di atas menunjukkan bagaimana desentralisasi mempunyai implikasi terhadap inflasi, meskipun terdapat kecenderungan perbedaan implikasi di negara berkembang dengan dengan implikasi di negara maju. Di negara maju, desentralisasi telah meningkatkan kredibilitas dan komitmen untuk stabilitas moneter, sementara di negara berkembang manfaat komitmen yang lebih besar dari desentralisasi belum diperoleh. Justru sebaliknya, desentralisasi di negara berkembang telah menimbulkan tekanan inflasi dari defisit anggaran yang lebih besar. Di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Brodjonegoro, et al. (2003), dengan adanya otonomi daerah, tugas otoritas moneter dalam menjaga target inflasi menjadi lebih berat karena sumber inflasi menjadi lebih menyebar dan lebih sulit dikontrol. KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI INDONESIA Aspek Hukum Koordinasi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Secara hukum, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku. Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan anggota Dewan Moneter yang ketuanya adalah Menteri Keuangan dan merupakan perwakilan pemerintah. Secara hukum, dengan kondisi tersebut tidak ada permasalahan koordinasi antara pemerintah dan BI karena BI merupakan mitra kerja di dalam Dewan Moneter. Namun karena BI termasuk bagian dari pemerintah, maka tidak terdapat lagi sistem pengendalian intern yang dapat mencegah pemerintah untuk membiayai defisitnya berasal dari BI. Pada periode tersebut, tidak sedikit BI memberikan kredit kepada pemerintah, lembaga pemerintah dan bank, seperti kredit kepada BULOG dan kredit likuiditas. Pemberian kredit tersebut merupakan penciptaan 58 uang baru oleh BI yang bersifat inflatoir sehingga dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun independen, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa pasal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, seperti pasal 55, ayat 1, menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dari perspektif pelaksanaan kebijakan moneter, pasal ini dapat diterjemahkan pembiayaan fiskal defisit harus memperhatikan tujuan akhir kebijakan moneter berupa stabilitas rupiah. Dalam ayat 4 pasal yang sama disebutkan BI dilarang membeli surat-surat utang negara di pasar primer. Pasal tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan agar pemerintah tidak membiayai fiskal defisit secara langsung dari bank sentral yang dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi. Berdasarkan undang-undang Bank Indonesia tersebut terlihat bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah diatur cukup baik, seperti terdapat pembatasan biaya fiskal defisit yang berasal dari Bank Indonesia. Selain itu, dalam penetapan inflasi sebagai tujuan akhir dari BI, pemerintah berkoordinasi dengan BI. Sementara itu, dari perspektif pelaksanaan kebijakan fiskal, pengaturan koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara eksplisit juga dituangkan dalam tatanan legal dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 21 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Lebih lanjut lagi pada pasal 12 UU tersebut, untuk mengangkat masalah disiplin fiskal bagi pemerintah pusat dan daerah, UU tersebut juga mengatur batas maksimum defisit fiskal serta pinjaman. Defisit pemerintah pusat dan daerah, masingmasing tidak diperkenankan melebihi batas maksimum 3% dari PDB dan PDRB. Pembatasan defisit tersebut serupa dengan Maastricht Treaty yang mensyaratkan batas maksimum defisit sebesar 3% PDB sebagai 59 pre-kondisi untuk masuk dalam European Monetary Union. Selanjutnya, pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing juga tidak diperkenankan melebihi treshold 60% dari PDB dan PDRB. Pasal 23 UU tersebut juga menjamin aspek prudensial dari pinjaman luar negeri, dimana seluruh hibah maupun pinjaman harus mendapat persetujuan dari parlemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU No. 17 tahun 2003 adalah bentuk legal kewajiban koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan sekaligus menjamin adanya tata kelola anggaran yang taat asas. Pasang Surut Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Seperti di negara-negara lainnya, tujuan kebijakan fiskal di Indonesia khususnya sejak PELITA I lebih ditekankan kepada mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dengan jalan memperluas kesempatan kerja. Seiring dengan meningkatnya pinjaman luar negeri, kebijakan fiskal juga diarahkan pada penyelesaian utang luar negeri dan dalam negeri untuk mencapai kondisi fiskal yang sustainable. Sementara itu, tujuan kebijakan moneter BI berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah tersebut mencakup inflasi dan nilai tukar rupiah. Pada masa sebelum UU tersebut dikeluarkan, tujuan BI selain menjaga kestabilan rupiah juga mencakup mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemberian kewenangan kepada BI hanya menstabilkan nilai rupiah agar BI lebih fokus dalam mencapai tujuannya dan sekaligus mengamankan atau mengendalikan kebijakan yang dapat membahayakan inflasi. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek melalui pembiayaan defisit dapat membahayakan inflasi dan stabilitas makro, sehingga dapat dinetralisir atau dikendalikan melalui kebijakan moneter yang cenderung ketat. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penekanan pada kedua kebijakan 60 tersebut, yaitu kebijakan moneter lebih menekankan kepada inflasi, sementara kebijakan fiskal lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dengan adanya perbedaan penekanan tujuan tersebut maka absennya koordinasi dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Dalam tataran praktis, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan dewasa ini, paling tidak, dijalankan melalui 4 aspek. (i) Koordinasi terkait dengan pengelolaan permintaan agregat Secara konseptual, aspek ini banyak berhubungan dengan pendekatan IS/LM dan pengaruhnya terhadap permintaan agregat. Aspek ini mendudukkan kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks koordinasi kebijakan makroekonomi dalam mempengaruhi permintaan agregat. Arah kebijakan moneter dan fiskal dipadukan agar tidak saling bertentangan untuk mempengaruhi sasaran akhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kombinasi kebijakan fiskal/moneter yang longgar dan atau ketat diharapkan akan menghasilkan hubungan harmonis dalam mencapai sasaran akhir tersebut. Dalam prkatek di Indonesia, hubungan ini antara lain tergambar pada penentuan asumsi indikator untuk penghitungan RAPBN. Dalam konteks pengelolaan makroekonomi, penentuan dan koordinasi asumsi APBN ini menggambarkan upaya menyatukan pandangan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh. Hal ini mengingat asumsiasumsi yang digunakan dalam APBN tersebut secara konseptual akan konsisten dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi. (ii) Koordinasi terkait upaya mengoptimalkan hubungan antar instrumen kebijakan fiskal dan moneter sehingga interaksi kedua kebijakan tersebut tidak menghasilkan paradoks. Secara konseptual, aspek ini akan banyak terkait dengan bentuk pembiayaan arah kebijakan yang akan ditempuh di aspek pertama. Pada aspek ini, bentuk pembiayaan perlu dicermati karena akan banyak mempengaruhi efektivitas kebijakan yang akan ditempuh. Beberapa paradoks dapat terjadi jika interaksi yang terjadi pada 61 aspek pembiayaan saling bertentangan. Terkait dengan pengendalian inflasi, konsep umum yang digunakan misalnya berhubungan dengan konsep unpleasant monetarist arithmetic (Sargent dan Wallace, 1981) yang kemudian berkembang menjadi konsep Fiscal Theory of Price Level (FTPL)3. Untuk praktik di Indonesia aspek ini tercermin pada struktur APBN. Hubungan antara suku bunga dan kinerja keuangan pemerintah terjadi melalui komponen penerimaan PPh non-migas, komponen pengeluaran dana alokasi umum (DAU) dan komponen pembayaran bunga utang domestik pemerintah (yang selanjutnya disebut bunga utang). Penerimaan PPh non-migas akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi pada suku bunga simpanan di bank. Pengeluaran DAU juga akan terpengaruh sejalan dengan perubahan penerimaan dalam negeri sebagai komponen perhitungan DAU akibat perubahan PPh non-migas tersebut. Sementara itu, pembayaran bunga utang akan berhubungan dengan pergerakan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang dijadikan pemerintah sebagai acuan kupon variable rate untuk surat utang negara. Dapat disampaikan bahwa hubungan suku bunga dan keuangan pemerintah tersebut secara implisit menggambarkan bahwa dampak kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga SBI kepada keuangan negara akan sangat dipengaruhi oleh (i) tingkat sensitivitas masing-masing komponen dalam APBN terhadap perubahan suku bunga dan (ii) sensitivitas dan linearitas perubahan suku bunga SBI terhadap suku bunga simpanan di perbankan. Tingkat sensitivitas dan karakterisitik hubungan suku bunga dan kinerja keuangan pemerintah tersebut pada akhirnya mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan defisit keuangan pemerintah. Potensi defisit ini dapat semakin meningkat bilamana dikaitkan dengan sensitivitas antara suku bunga SBI dan suku bunga simpanan yang terkadang tidak terjadi secara linear sehingga dapat mempengaruhi potensi penerimaan PPh non-migas. 3 62 Beberapa literature terkait FTPL lihat Leeper (1991), Koncherlakota and Phelan (1999), Cochrane (1998), Woodford (1996, 2001) dan Walsh (2003) Dalam kaitannya dengan implikasi bagi kebijakan moneter, kondisi ini dapat menempatkan kebijakan moneter dalam posisi dilematis mengingat pada saat ini kondisi fiskal masih dalam tahap konsolidasi untuk menurunkan beban utang yang masih tinggi. Praktik lain pada aspek ini yang perlu mendapat perhatian dalam konteks koordinasi kebijakan fiskal dan moneter adalah peran SBI sebagai instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) dalam kebijakan moneter. Dalam konteks anggaran pemerintah dan bank sentral yang terkonsolidasi, penggunaan instrumen ini akan memberikan dampak berbeda dengan konsep umum yang ada. Penggunaan instrumen hutang bank sentral ini secara konseptual dapat menimbulkan paradoks dalam kebijakan moneter di jangka panjang. Hal ini terutama terkait dengan beban bunga yang harus dibayar bank sentral yang dalam praktiknya dapat dikategorikan sebagai pencetakan uang oleh bank sentral. Dalam kondisi kebijakan fiskal tidak menyerap tambahan uang tersebut melalui peningkatan pajak, maka penggunaan instrumen ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi di periode mendatang. (iii) Koordinasi lain terkait dengan kemampuan kebijakan fiskal khususnya melalui subsidi dalam menyerap resiko suatu gejolak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk praktik di Indonesia, konsep ini antara lain terkait dengan peran subsidi BBM dan pengelolaan pasokan kebutuhan pokok. Untuk subsidi kebutuhan pokok, kajian untuk kasus di Indonesia berimplikasi pengelolaan terhadap distribusi dan pasokan kebutuhan pokok oleh pemerintah menjadi sangat penting artinya dalam pengendalian inflasi di Indonesia. (iv) Koordinasi terkait dengan contigency plan dalam memantapkan stabilitas keuangan, moneter, dan makroekonomi yang berasal dari gejolak perekonomian. Secara konseptual, hubungan koordinasi ini terkait dengan pencegahan atau strategi untuk meminimalkan dampak negatif dari guncangan perekonomian yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi dan 63 membahayakan kelangsungan (sustainability) perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bercermin pada krisis ekonomi tahun 1997/98 yang berawal dari external shock, krisis nilai tukar dan perbankan yang telah menggoyahkan perekonomian nasional memberikan pelajaran tentang pentingnya memiliki contigency plan dalam mencegah terjadinya ketidakstabilan makroekonomi. Misalkan pengaturan fasilitas pembiayaan darurat kepada perbankan nasional dari pemerintah merupakan langkah maju dalam rangka mencegah terjadinya resik sistemik krisis perbankan dari satu bank ke bank yang lain. Contigency plan tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada pemeliharaan stabilitas makroekonomi. Misalnya strategi meminimalkan dampak dari meroketnya kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan perekonomian melalui pembentukan Sovereign Welfare Fund (SWF) atau strategi lainnya. Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dewasa ini masih menghadapi berbagai kendala yang menjadikan interaksi kedua kebijakan makroekonomi belum optimal. Kendala tersebut antara lain terkait dengan hubungan struktural bentuk interaksi kebijakan moneter fiskal itu sendiri. Kendala optimalisasi koordinasi kebijakan juga mengemuka terkait dengan lingkungan kondisi perekonomian yang belum menguntungkan serta beberapa permasalahan teknis dan operasional. Salah satu permasalahan struktural yang mengemuka dewasa ini adalah penggunaan SBI sebagai instrumen OPT. Kondisi ini secara struktural dalam jangka menengah panjang akan membebani dan menempatkan kedua kebijakan makroekonomi tersebut dalam posisi dilematis. Upaya menyerap kelebihan likuiditas oleh Bank Indonesia yang konsisten dengan upaya pengendalian inflasi akan menimbulkan beban bagi neraca bank sentral dan perekonomian di masa mendatang. Beban bagi bank sentral adalah peningkatan biaya bunga SBI yang akan meningkatkan resiko neraca bank sentral. Beban ini kemudian dapat mengalir dan membebani kebijakan 64 fiskal (APBN) jika resiko neraca bank sentral tersebut terus meningkat dan harus ditutupi oleh dana dari APBN. Dalam konteks perekonomian secara lebih luas, penggunaan SBI berpotensi memberikan tekanan inflasi ke depan jika beban bunga riil SBI meningkat lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Resiko peningkatan inflasi ke depan semakin besar jika pada saat bersamaan penyerapan likuiditas yang bersumber dari pajak relatif tidak elastis. Premis dan permasalahan struktural penggunaan SBI dalam konteks koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ini, sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya, menunjukkan bahwa penggunaan SBI sebagai instrumen OPT dalam kebijakan moneter juga memiliki resiko memberikan tekanan inflasi ke depan. Hasil simulasi ini berbeda jika Bank Indonesia menggunakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau T-Bills sebagai instrumen dalam OPT. Hal ini terjadi karena peningkatan beban utang yang timbul dari OPT akan direspon secara aktif oleh kebijakan fiskal dengan meningkatkan pajak. Dalam kondisi potensi kenaikan uang beredar dapat diserap oleh pajak, kebijakan moneter ketat yang ditempuh Bank Indonesia akan secara permanen menurunkan inflasi ke depan. Penggunaan SBI sebagai instrumen OPT tersebut secara konseptual dapat diklasifikasikan sebagai pembentuk quasi fiscal deficit di Indonesia. Permasalahan struktural yang juga perlu dicermati dalam konteks koordinasi dan interaksi kebijakan fiskal dan moneter adalah terkait dengan dampak arah kebijakan moneter terhadap beban bunga utang domestik pemerintah. Menggunakan alur analisa Loyo (1999), Favero dan Giavazzi (2004) dan Blanchard (2004), argumen tersebut terkait dengan dampak kebijakan moneter ketat melalui peningkatan suku bunga terhadap peningkatan beban pembayaran bunga utang domestik pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan defisit keuangan pemerintah, ceteris paribus. Bilamana defisit ini dibiayai dengan penerbitan utang pemerintah domestik sementara pada saat bersamaan kinerja fiskal masih belum 65 stabil maka kondisi ini akan diterjemahkan sebagai peningkatan resiko kesinambungan fiskal oleh pelaku pasar. Peningkatan resiko tersebut selanjutnya dapat berimplikasi kurang menguntungkan terhadap nilai tukar. Inflasi akan berada dalam tekanan bilamana tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut. Dalam keadaan bank sentral merespon pelemahan nilai tukar dan potensi peningkatan inflasi ini dengan menaikkan kembali suku bunga maka permasalahan akan berulang dan meningkat sehingga menempatkan kebijakan moneter dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menempatkan kebijakan moneter dalam posisi dilematis dalam pengendalian inflasi. Berbagai indikator mengindikasikan hal yang hampir sama dengan argumen di atas. Persepsi resiko pelaku pasar yang didekati dengan indikator yield spread antara Yankee bond dan US T-notes menggambarkan gerakan yang hampir searah dengan rasio utang pemerintah. Hal ini secara implisit menggambarkan upaya menutupi defisit dengan penerbitan utang pemerintah akan disikapi secara berhati-hati oleh pelaku pasar karena ditengarai dapat mengganggu prospek kesinambungan fiskal. Sikap tersebut kemudian berimplikasi kepada keputusan pelaku pasar dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar. Data pasca September 1997 mengindikasikan bahwa persepsi resiko memiliki hubungan yang positif dengan pergerakan nilai tukar. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dewasa ini juga menjadi kurang optimal dan dilematis karena pada saat bersamaan lingkungan ekonomi domestik dan global masih kurang menguntungkan. Lingkungan domestik yang masih mengalami ekses likuiditas perbankan dan konsistensi Bank Indonesia mengendalikan likuiditas perbankan agar tetap sesuai kebutuhan perekonomian mengakibatkan beban OPT terus mengalami peningkatan. Beban ini semakin meningkat karena pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tambahan likuiditas secara optimal. Berbagai kondisi ini berpotensi semakin memperberat resiko neraca bank sentral dan secara keseluruhan dapat mengurangi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. 66 Lingkungan global yang kurang menguntungkan juga terkait dengan perkembangan harga komoditi dan pasar finansial global. Harga komoditi global seperti beras dan CPO yang meningkat memberikan beban tersendiri kepada kebijakan fiskal. Pengurangan bea masuk berbagai komoditas industri dan pemberian subsidi kebutuhan pokok mempengaruhi kesinambungan fiskal. Pada sisi lain, tekanan kenaikan harga komoditi global tersebut berpotensi memberikan tekanan secara permanen terhadap inflasi domestik. Respon kebijakan moneter ketat terkait dengan dampak harga komoditi global ini menjadi dilematis karena pada sisi lain upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertimbangan kebijakan fiskal. Lingkungan pasar finansial yang mengalami ekses likuditas juga menjadi tantangan sendiri bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Arus modal masuk yang saat ini cukup besar mengharuskan kebijakan moneter dan fiskal lebih kuat. Kebijakan moneter yang ditempuh diarahkan agar tidak terjadi posisi hard landing perekonomian pada saat terjadi penyesuaian perilaku arus modal global. Sementara, prospek kesinambungan fiskal harus tetap dijaga mengingat perilaku investor global juga mencermati kinerja dan prospek kebijakan fiskal. Kendala lain yang mengakibatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi belum optimal antara lain terkait dengan beberapa permasalahan teksnis dan operasional. Peran daerah yang saat ini meningkat sejalan dengan pemberian otonomi daerah memberikan tantangan dalam mengkonsolidasikan kebijakan fiskal dalam konteks pemerintahan secara umum (general government) dengan arah kebijakan moneter. Proses penyusunan APBD yang raltif lebih lambat dibandingkan APBN dapat menghambat penentuan arah umum kebijakan makroekonomi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga terhambat terkait proses politik di parlemen baik di tingkat daerah maupun pusat pada saat penetapan APBN dan APBD yang relatif cukup lama. Kondisi ini akan memberikan dampak kesenjangan waktu (in side lag and out side time lag) terhadap efektivitas timing dan magnitude kebijakan makroekonomi yang akan ditempuh. 67 Berbagai studi empiris untuk melihat manfaat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh Mochtar (2003, 2004, 2005), Goeltom dan Simorangkir (2005), Hermawan and Munro (2007), serta Goeltom dan Hermawan (2007). Goeltom dan Simorangkir (2005) menganalisis koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia dari tahun 1970-2002 dengan menggunakan model teori permainan (game theory). Fungsi tujuan dari pemerintah dan Bank Indonesia adalah meminimalkan kerugian kesejahteraan masyarakat (loss function) dari perbedaan target pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan aktualnya. Perbedaan mendasar dari fungsi tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal memberikan bobot yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi dibandingkan inflasi, sebaliknya kebijakan moneter memberikan bobot yang lebih besar terhadap inflasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Temuan pokok dari hasil simulasi game theory antara lain: (i) Pembiayaan fiskal defisit yang berasal dari Bank Indonesia dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan laju inflasi dan stabilitas makroekonomi, (ii) Kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif atau mengutamakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan masyarakat (social loss) yang lebih besar terhadap perekonomian, (iii) Kebijakan moneter yang terlalu ketat atau mengutamakan inflasi tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan masyarakat yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia, dan (iv) Koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memberikan kerugian kesejahteraan masyarakat yang lebih kecil terhadap perekonomian dibandingkan jika tidak berkoordinasi. Studi lanjutan dilakukan oleh Hermawan dan Munro (2007), yang mempelajari interaksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia dalam kerangka model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) yang disesuaikan dengan karakterisitik prekonomian terbuka dan negara berkembang, dalam tiga periode yang berbeda yaitu 19912006, paska nilai tukar mengambang 1998-2006, dan paska krisis 200068 2006. Hasil studi melalui eksperimen simulasi stokastik menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas perekonomian atau bersifat countercyclical, dan peran aktif tersebut bersama-sama dengan kebijakan moneter telah menghasilkan loss function yang minimum bagi perekonomian. Dengan perkataan lain, otoritas moneter untuk jangka pendek dapat mentolerir inflasi yang sedikit lebih tinggi demi menjaga momentum pertumbuhan output. Analisis terkini oleh Goeltom dan Hermawan (2007) dengan pendekatan yang sama berupaya melihat respons moneter atas berbagai skenario kebijakan fiskal sebagai akibat shock yang tidak terantisipasi. Dalam hal ini, skenario-skenario tersebut merupakan alternatif kebijakan fiskal yang dapat ditempuh untuk menghadapi tekanan APBN akibat peningkatan harga minyak dunia terkait dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah yang berdampak ekspansif, kontraktif, maupun kebijakan pengurangan subsidi. Khusus mengenai kebijakan pengurangan beban subsidi yang menimbulkan tekanan inflasi ,studi ini menekankan perlunya kecermatan kebijakan moneter yang umumnya cenderung ketat. Hasil studi menunjukkan bahwa respon optimal melalui peningkatan suku bunga untuk meredakan dampak peningkatan harga domestik dan selanjutnya memperbaiki output, ternyata memiliki dampak ikutan dalam bentuk penurunan daya beli atau konsumsi rumah tangga miskin yang dapat berlangsung cukup lama, yakni sekitar sepuluh kuartal. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi kesejahteraan masyarakat luas. Terindikasikan akan pentingnya bauran kebijakan fiskal dan moneter dilakukan dengan memperhitungkan momentum yang tepat, dimana kebijakan pengurangan subsidi BBM sebaiknya dilakukan pada saat inflasi berada ada tingkat yang rendah dan pertumbuhan ekonomi berada tingkat yang relatif tinggi. 69 PEMIKIRAN MENGENAI ARAH KOORDINASI KEBIJAKAN KE DEPAN Mengamankan manfaat koordinasi kebijakan di lingkungan ketidakpastian Dari berbagai studi empiris yang dilakukan penulis, terlihat bahwa Otoritas moneter maupun fiskal dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, dan terukur dalam melaksanakan kebijakannya masing-masing, sehingga signal kebijakan yang disampaikan dapat direspons secara positif oleh pelaku ekonomi. Jika koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terjaga dengan baik, maka manfaat dari koordinasi kebijakan dapat segera dipetik seperti terciptanya kestabilan makro, meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi atas Indonesia, semakin mudahnya akses kepada pasar finansial global, serta semakin mudahnya akses kepada pasar finansial global, serta naiknya peringkat Indonesia di dunia internasional; di mana semua itu pada hakekatnya akan berujung pada peningkatan peluang peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, indahnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan sangat tampak di saat perekonomian Indonesia menghadapi ketidakpastian dan gejolak eksternal, misalnya dalam bentuk shock harga minyak ataupun nilai tukar. .RRUGLQDVL ¿VNDO GDQ PRQHWHU KDUXV PHQJDFX NHSDGD XUXWDQ (sequence ¶WLQGDNDQ NHELMDNDQ¶ GL PDQD VDODK VDWX RWRULWDV KDUXV PHODKLUNDQNHELMDNDQWHUOHELKGDKXOXEHUGDVDUNDQWDQWDQJDQVSHVL¿NGL EDZDKRWRULWDVQ\D\DQJEHUDVDOGDULOLQJNXQJDQHNVWHUQDOEDUXNHPXGLDQ GLUHVSRQ ROHK NHELMDNDQ RWRULWDV ODLQQ\D 3DGXDQ NHELMDNDQ KDUXV PHPSHUWLPEDQJNDQ NHQGDOD NHUDQJND XQGDQJXQGDQJ VHUWD NHUDQJND RSHUDVLRQDOQ\D3HUNHPEDQJDQGDQWDQWDQJDQHNRQRPLJOREDOPHPEXDW NRQWHNVSHODNVDQDDQPRGHONRRUGLQDVL’leader-follower¶LQLKDUXVOHELK GLODWDUEHODNDQJLROHKGLQDPLNDshocksDWDXNHMXWDQ\DQJWHUMDGL'HQJDQ GHPLNLDQtujuan akhir dari koordinasi kebijakan ini tidak akan membuat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dikorbankan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, shocks yang dialami Indonesia umumnya datang dari lingkungan eksternal. Adalah sebuah kenyataan, 70 bahwa saat ini kita hidup di tengah perekonomian dunia yang terintegrasi. Bertumpu pada komoditas, barang manufaktur, dan jasa unggulan, Indonesia dapat memanfaatkan integrasi ekonomi dunia tersebut demi kemakmuran bangsa. Komoditas, barang manufaktur, dan jasa unggulan tersebut dapat memenangkan persaingan di tingkat global tidak hanya karena kelimpahannya saja di bumi Indonesia, namun hal tersebut merupakan cermin produktivitas agen ekonomi domestik. Jika kita percaya buah dari keterbukaan perekonomian adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan dan kontinuitasnya. Hal utama yang menjadi ancaman dari keterbukaan ekonomi adalah volatilitas serta ketidakpastian ekonomi internasional. Bagi Indonesia dengan skala perekonomian kecil dan terbuka, ketidakpastian ekonomi global antara lain tercermin dari dinamika nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Adakalanya agen ekonomi domestik dapat menduga gerak nilai tukar Rupiah ke depan, namun di saat lain geraknya menjadi tidak sesuai prakiraan. Semua itu menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal sehingga kepentingan perekonomian domestik tidak terganggu. Paduan indah dan optimal dari koordinasi kebijakan moneter dan fiskal harus bertujuan untuk mengamankan benefit perekonomian yang telah dinikmati agen ekonomi domestik, buah dari keterbukaan ekonomi. Saat ini koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat dikatakan relatif berjalan lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Menghadapi shock kenaikan harga minyak yang mendekati USD100/barrel pada tahun 2007, serta kegoncangan pasar dunia sebagai akibat dari masalah pinjaman subprime di Amerika, kestabilan makroekonomi Indonesia terbukti dapat terjaga dengan baik. Sumbangan penting bagi kestabilan makroekonomi tersebut datang dari kebijakan otoritas fiskal dalam merealokasi pos anggaran dan kebijakan yang mengarah pada penurunan hutang pemerintah. Hasil simulasi dalam studi Goeltom dan Hermawan (2007) mendukung peran penting kebijakan otoritas fiskal tersebut dalam 71 merespon shock harga minyak, seraya mempertahankan agar daya beli pelaku ekonomi domestik tidak turun. Kebijakan tersebut menumbuhkan kredibilitas otoritas fiskal di tengah gejolak pasar dunia saat ini, dan sebagai akibatnya arah perekonomian saat ini tidak memerlukan respon kebijakan moneter lanjutan yang signifikan4. Selain itu, data menunjukkan kesehatan fiskal yang cukup signifikan dalam hal terjaganya defisit APBN di bawah angka 3%, dan menurunnya beban hutang pemerintah sejak tahun 2000, terutama pinjaman luar negeri. Terdapat dua hal penting yang harus segera diwujudkan menghadapi tantangan ke depan, dalam konteks untuk meletakkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam tataran yang sangat strategis. Pertama, bahwa otoritas fiskal dan moneter perlu mulai merintis sebuah contigency plan dengan tujuan utama menjamin benefit perekonomian yang sudah diraih tidak serta merta hilang seperti pengalaman krisis 1997 – 1998 lalu. Contigency plan harus berisi penjabaran detil langkah-langkah pelaksanaan kebijakan masing-masing otoritas di saat genting. Apabila mengacu kepada salah satu bentuk koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks leader–follower, maka hal utama yang menjadi perhatian adalah bentuk dan sumber permasalahan yang hendak dipecahkan. Suatu ketika, shock ekonomi akibat kenaikan harga minyak, menuntut otoritas fiskal mengubah kebijakan pengeluaran pemerintah dengan segera. Di saat seperti itu, otoritas moneter menjadi ’follower’ dengan melakukan kebijakan moneter yang seharusnya tidak bersifat mengganggu stabilitas makroekonomi. Di suatu saat lain, shock ekonomi datang dalam bentuk tekanan pada sektor eksternal dan karena fenomena J-curve maka nilai tukar menjadi tertekan. Di saat tersebut otoritas moneter harus segera melahirkan kebijakan moneter sebagai respon stabilisasi perekonomian, dan otoritas fiskal pun menjadi ’follower’ dengan menetapkan kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan stabilitas makroekonomi. Prasyarat 4 72 Inflasi November 2007 tercatat sebesar 0,18% (mtm), lebih rendah daripada pola historisnya (0,38%, mtm). Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 6,71% (yoy) atau lebih rendah disbanding bulan sebelumnya (6,88%). Dengan perkembangan tersebut, inflasi ytd s.d. bulan November 2007 mencapai 5,43%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (5,27%). bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut adalah optimalitas dalam hal timing, besaran, dan arah kebijakannya. Namun perlu diingat bahwa apabila shock yang terjadi dipandang terlalu kecil, maka tidak perlu ada mekanisme ’leader-follower’ tersebut. Sehingga dalam kerangka contigency plan yang hendak disusun, terdapat pula ukuran atau level dari shocks. Hal ini penting untuk menjadi dasar pembentukan contigency plan sebab bila ukuran atau level dari shock tersebut terlewati maka apabila tidak ada protokol yang mengatur respon optimal kebijakan, dan koordinasi tidak direncanakan dalam satu rangkaian perencanaan, maka respon dari sebuah otoritas akan menjadi ’terlalu besar’ dari porsi yang seharusnya. Akibatnya, otoritas yang lain terpaksa merespon dengan kebijakan yang tidak optimal. Pengalaman juga mengajarkan bahwa contigency plan harus dilengkapi dengan langkah kebijakan yang bersifat preventif dan juga kuratif untuk menangkal dampak negatif dari arus modal keluar dalam skala besar yang dapat terjadi secara tiba-tiba akibat dari integrasi ekonomi global. Kongkritnya, paduan kebijakan yang bersifat preventif dapat berupa koordinasi moneter dan fiskal untuk terus mempertahankan kestabilan makroekonomi secara konsisten, penciptaan atmosfir yang baik bagi Penanaman Modal Asing (foreign direct investment atau FDI) serta pengembangan infrastruktur. Sangat beralasan apabila dalam kebijakan yang bersifat preventif termuat upaya untuk membangun mekanisme pengaturan swap secara bilateral dengan negara-negara partner dagang di kawasan Asia. Selanjutnya, kerangka kebijakan preventif lain juga harus menyentuh rancang bangun sektor finansial melalui forum stabilitas sistem keuangan (FSSK), dengan tujuan untuk menyehatkan agen ekonomi di dalamnya serta memperdalam sekaligus memperluas struktur pasar finansial. Sejalan dengan upaya tersebut, FSSK juga harus mendorong pelaku ekonomi untuk mulai melakukan lindung nilai (hedging) atas posisi keuangan mereka yang beresiko atas nilai tukar. Selain itu, upaya monitoring dan pemantauan dini atas kondisi sektor finansial harus menjadi bagian penting dari detil contigency plan. 73 Sedangkan detil contigency plan berupa kebijakan yang bersifat kuratif sangat berkaitan dengan upaya stabilisasi ekonomi jangka sangat pendek; dimana shock dalam perekonomian Indonesia bermanifestasi menjadi keadaan yang benting. Cirinya sudah dikenal, yakni larinya modal asing dalam jumlah besar secara tiba-tiba, serta melemahnya nilai tukar Rupiah secara mendalam, melonjaknya inflasi, serta runtuhnya ekspektasi rasional pelaku ekonomi domestik dan asing. Jika demikian yang terjadi, maka perekonomian Indonesia sudah masuk fase genting dalam kategori krisis ekonomi dimana dampak negatifnya dirasakan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Otoritas moneter dan fiskal harus bahu-membahu dengan cerdik di saat genting tersebut. Namun, itu saja tidak cukup, karena pengalaman krisis 1997-98 yang lalu menunjukkan bahwa apabila stabilitas pasar keuangan sudah terancam secara sistemik maka diperlukan crisis management protocol yang melibatkan pimpinan tertinggi negara ini sebagai legitimasi politik yang menyepakati perlunya tindakan luar biasa – misalnya bail-out sistem keuangan – sebagai dasar bagi otoritas moneter dan fiskal untuk menggunakan dan menciptakan instrumen-instrumen khusus masa krisis. Selanjutnya, paduan kebijakan moneter dan fiskal yang optimal dalam saat-saat genting harus memuat langkah-langkah yang terukur dalam peningkatan intensitas intervensi langsung di pasar valuta asing dan obligasi. Saat-saat tersebut juga menuntut peningkatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan, guna mengurangi efek lanjutan dari risiko sistemik di sektor finansial secara drastis. Standar kebijakan dari otoritas moneter mengatasi drastisnya pelarian modal asing adalah dengan menggunakan instrumen suku bunga seperti di tahun 1998. Namun, hal tersebut belum cukup karena kebijakan otoritas moneter harus didukung kebijakan otoritas fiskal dan pemerintah secara kongkrit yang berkaitan dengan upaya menenangkan kepanikan pelaku ekonomi di pasar keuangan dan barang. Sehingga prioritas sasaran kebijakan kuratif dalam situasi genting adalah: pertama, mencegah pelarian arus modal asing dan tertekannya nilai tukar Rupiah agar tidak berlanjut dengan kebijakan suku bunga yang terukur serta intervensi di pasar valuta asing oleh Bank 74 Indonesia, diiringi dengan intervensi terbatas dan terukur oleh otoritas fiskal di pasar obligasi dan saham, kedua, mengembalikan ketenangan pelaku ekonomi di sektor keuangan dengan koordinasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan dalam keadaan emergency. Hal ini akan menenangkan para pemilik tabungan agar tidak rush melakukan penarikan dan besar-besaran seketika. Ketiga, penggiringan opini publik dengan komunikasi yang fokus dan jelas dari kedua otoritas secara bersama-sama. Perlu dihindarkan pernyataan yang simpang siur sehingga membingungkan pelaku ekonomi. Kemudian sasaran keempat, adalah menjamin kelancaran distribusi bahan-bahan pokok di seluruh pelosok Indonesia. Kedua, perlu mulai dipikirkan mengenai keberadaan semacam dana yang disebut sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki fungsi stabilisasi, investasi, maupun tabungan. Ke depan, hal ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi global bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk ketidakpastian yang semakin tinggi terutama di sektor keuangan. Kecanggihan produk pasar keuangan melahirkan tantangan tersendiri baik bagi otoritas moneter maupun fiskal. Di masa depan bentuk dari shocks datang dari pasar keuangan global dan persoalan geo-politik. Produk pasar keuangan dunia pun telah berkembang menyentuh pasar komoditas internasional dengan sekuritisasi surat-surat jual beli komoditas. Hal tersebut makin merumitkan perdagangan komoditas internasional karena komoditi menjadi sebuah asset-class tersendiri yang menjadi setara dengan aset finansial di pasar keuangan. Perdagangan komoditas internasional tiba-tiba menghadapi kenyataan bahwa harga pasar tidak lagi semata-mata ditentukan oleh permintaan atas ekspor dan impor namun terlebih lagi oleh ekspektasi pelaku pasar keuangan atas harga sekuritisasi surat-surat jual beli barang komoditas. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa hedge funds dan palaku pasar finansial internasional mulai meramu produk derivatif yang memiliki underlying sekuritisasi surat-surat jual beli pasar komoditas internasional. Sebagai negara yang memiliki keunggulan dan kelimpahan komoditas untuk ekspor, Indonesia rentan terhadap perkembangan terakhir di pasar 75 internasional. Perkembangan pesat ini menuntut koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memiliki kreativitas dalam mempertahankan perannya menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah bersama bank sentral harus mulai menyusun rencana kongkrit pembentukan SWF. Pada dasarnya SWF harus dikelola dengan satu tujuan, yakni perolehan hasil yang optimal. Keleluasaan yang lebih longgar dalam pengelolaannya, merupakan kelebihan SWF dibandingkan dengan pengelolaan cadangan devisa oleh bank sentral. Dana SWF dapat bersumber dari penghasilan pemerintah dari minyak atau komoditi. Sebaiknya, pengelola SWF adalah sebuah badan otonom resmi pemerintah yang khusus dibentuk dengan dasar kerja seperti layaknya lembaga keuangan internasional modern. Mandat yang diberikan kepada pengelola SWF adalah pengelolaan kapital dengan tujuan meraup laba, tanpa embel-embel politik. Berdasarkan pengamatan, berbagai negara yang memiliki kelimpahan endowment komoditi minyak dan lainnya, seperti Uni Arab Emirat, Singapura, Rusia, China, telah mulai membentuk SWF masing-masing, atas surat-surat jual beli komoditi minyak. Hasil kelola SWF yang diperoleh dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk paling sedikit tiga kategorisasi. t ,BUFHPSJQFSUBNBQFNFSJOUBIEBQBUNFOHHVOBLBOIBTJMLFMPMB48' sebagai dana stabilisasi di saat shock ekonomi global mengganggu kredibilitas anggaran fiskal salam bentuk gejolak harga komoditas minyak sebagaimana yang dialami Indonesia di masa lampau. SWF juga dapat digunakan untuk mendorong program stabilisasi yang mengancam kestabilan sektor keuangan. t ,BUFHPSJLFEVBIBTJMLFMPMBEBOB48'EBQBUNFOKBEJTFNBDBNsaving funds dengan perspektif jangka panjang. Dana dapat dipergunakan secara terencana untuk pemberdayaan pembangunan ekonomi melalui pembangunan usaha menengah, kecil, dan mikro sekaligus menjadi motor penggerak kegiatan promosi produk mereka di kancah perekonomian internasional. Strategi pengembangan industri manufaktur domestik juga dapat memanfaatkan sumber dana SWF 76 bagi program pengembangan sumber daya manusianya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja serta peningkatan skill. Kegunaan lain dalam kategori ini adalah sumber dana bagi upaya pelestarian sumbersumber daya alam yang dapat cepat habis. Selanjutnya, mengacu kepada pengalaman negara-negara maju maka hasil kelola dana SWF dapat dipakai sebagai sumber dana yang menjamin kesejahteraan di masa depan, di saat struktur demografi Indonesia berubah akibat dari membaiknya kualitas kehidupan (aging population). Dalam jangka panjang, harus ada jaminan bagi kelompok penduduk Indonesia yang tidak lagi produktif berupa dana pensiun dan tunjangan kesehatan yang memadai, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan. SWF juga akan memberi peluang bagi Indonesia di masa depan saat terjadi pergeseran dari penggunaan komoditas minyak yang semakin langka kepada energi alternatif. Di saat kecenderungan tersebut mulai berlaku maka akan tersedia dana cadangan masa depan bagi kontigensinya. Bahkan dana SWF dalam kategori ini dapat dipergunakan bagi pengembangan produk alternatif pengganti minyak dengan memanfaatkan kelimpahan produk pertanian yang mendukung sperti pohon jarak, jagung, dan lain sebagainya. t 4FEBOHLBOLBUFHPSJLFUJHBTFCBHJBOIBTJMLFMPMBEBOB48'EBQBUQVMB difokuskan secara murni bagi keperluan investasi dengan harapan di masa depan pemerintah memiliki modal yang lebih besar lagi untuk mewujudkan semua tujuan di atas. Pada akhirnya, melihat tantangan ke depan yang semakin berat, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal harus senantiasa diupayakan secara konsisten dengan memperhitungkan kapasitas ekonomi dan skala prioritas, serta diletakkan di dalam dimensi kebijakan makroekonomi yang terintegrasi, yaitu dengan merujuk pada upaya untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan untuk menjaga stabilitas makro serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (striking the optimal balance). 77 Ada keniscayaan sederhana bahwa nilai koordinasi itu mahal. Kalaupun dalam pelaksanaannya disertai dengan munculnya ’trade-off’ antara pencapaian stabilitas dan perumbuhan ekonomi, maupun ’paradox’ antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia, hal tersebut pada dasarnya merupakan fenomena jangka pendek, tidak dalam jangka menengah panjang. Dengan demikian, dengan dilandasi oleh spirit ’striking the optimal balance’, dengan pencapaian stabilitas makroekonomi, dukungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi dapat senantiasa terjaga baik. Dasar stabilitas ekonomi hanyalah merupakan salah satu ’element of continuity’ dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi seutuhnya. Dan karenanya, stabilitas makroekonomi yang telah diraih dalam beberapa waktu terakhir ini bukanlah merupakan sesuatu yang datang begitu saja, namun lebih sebagai buah dari tahapan langkah-langkah kebijakan ekonomi makro yang selama ini dilakukan secara terkoordinasi, prudent, terukur, dan berorientasi ke depan (forward-looking). Hal ini tentunya harus senantiasa kita jaga dan matangkan bersama-sama dengan langkah-langkah yang kongkrit di sektor ekonomi lain, sehingga momentum pembangunan yang tercipta melalui stabilitas makroekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangkitkan sektor riil, yang akhirnya akan menyejahterakan rakyat banyak. Di luar itu, dalam kaitannya dengan upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan dimensi kesejahteraan masyarakat yang merata, tantangan yang mengemuka saat ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan koordinasi kebijakan dalam era otonomi daerah, sehingga manfaat positif dari stabilitas ekonomi makro serta kebijakan desentralisasi yang ditetapkan juga dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dilandasi atas kompleksitas dari implikasi desentralisasi terhadap stabilitas harga, maka otoritas moneter dan fiskal baik di pusat maupun di daerah harus melakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber dayanya. Revitalisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan pemerintah daerah 78 baik dalam pengendalian inflasi itu sendiri maupun dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, koordinasi kebijakan yang konsisten di antara otoritas moneter dan fiskal , baik di pusat maupun daerah, akan dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi secara optimal, sehingga dapat memberikan berbagai manfaat baik secara politik maupun secara ekonomi seperti yang kita harapkan semua. 79 Daftar Pustaka Andersen, Torben M. (2005), “Fiscal Stabilization Policy in a Monetary Union with Inflation Targeting. Journal of Macroeconomics, 27, pp. 1-29. Barro, R.J. and D.B. Gordon (1983), “Rules, Discretion, and Reputation in a Model of Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, 12. Bennet, Herman dan Norman Loayza (2002), “Policy Biases When The Monetary adnd Fiscal Authorities Have Different Objectives”, on Monetary Policy: Rules and transmission Mechanism, Norman Loayza and Klaus Schmidt-Hebbel (eds), Central Bank of Chile. Blanchard, Olivier (2004), “Fiscal Dominance and Inflation Targeting: Lesson from Brazil” NBER Working Paper, 10389, Maret. Blinder, Alan S. (1982), “Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy”, NBER Working Paper, No. 982. Boediono (2007), “Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi – Universitas Gadjah Mada. Februari. Brodjonegoro, Bambang P.S., Iskandar Simorangkir, B. Yulianita, dan T.A. Falianty (2003), “Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Inflasi Regional dalam Era Otonomi”, Working Paper, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI dan Universitas Indonesia. Dodge, David. (2002), “The Interaction between Monetary and Fiscal Policies”, The Donald Gow Lecture, School of Policy Studies, Queen’s University, April. Favero, Carlo A. and Fransesco Giavazzi (2004), “Inflation Targeting and Debt: Lesson from Brazil”, NBER Working Paper, 10389, Maret. Goeltom, Miranda S. and Iskandar Simorangkir (2005), “Monetary and Fiscal Synergy in Indonesia”, Working Paper, Bank Indonesia. 80 Goeltom, Miranda S. and Danny Hermawan (2007), “Respon Optimal Kebijakan Moneter terhadap Shock Fiskal, pendekatan New Keynesian Open Macroeconomics”, Mimeo, Bank Indonesia, December Javed, Zahoor Hussain and Ahmet Sahinoz (2005), “Interaction of Monetary and Fiscal Policy in Case of Turkey”, Journal of Aplied Science, Asian Network for Scientific Information. Kydland, F.E. and E.C. Prescott (1977), “Rule Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85. Leeper, Eric M. (1991), “Equilibria under ‘Active’ and ‘Passive’ Monetary and Fiscal Policies”, Journal of Monetary Economics, 27, February Loyo, E (1999), “Tight Money Paradox on the Loose: A Fiscalist Hyperinflation”, mimeo, Kennedy School of Government, Juni. Mochtar, Firman (2003), ”SBI, T-Bills dan Pengendalian Inflasi”, Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Vol.3 No.6. _____________ (2004), ”Fiscal and Monetary Policy Interaction: Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia”, Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Vol. 7(3). _____________ (2005), ”Keterkaitan antara Suku Bunga dan Keuangan Pemerintah serta Implikasinya bagi Kebijakan Moneter”, Ulasan Pojok, Biro Kebijakan Moneter-Bank Indonesia, Volume II Nomor 5 , Maret. Mohanty, M.S. and Michela Scatigna (2004), Countercyclical Fiscal Policy and Central Bank, BIS Working Paper. Petit, Maria Luisa (1989), “Fiscal and Monetary Policy Coordination: A Differential Game Approach”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 4 (2). 81 PPSK-BI dan InterCAFE-IPB. (2006), “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah dan Sektor Keuangan Daerah”, Mimeo, Bank Indonesia. Roisland, Oystein dan Ragnar Trovik. (2000), “Fiscal Policy under Inflation Targeting”, Arbeidsnotat, 2000/15, Norges Bank. Sakamoto, Takayuki (2007), “Fiscal-Monetary Policy Mix: An Investigation of Political Determinants of Macroeconomic Policy Mixes”, Mimeo, Southern Methodist University. Sargent, Thomas and Neil Wallace (2005), “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5, Fall. Traclet, Virginie (2004), “Monetary and Fiscal Policies in Canada: Some Interesting Principles for EMU?”, Working Paper, Bank of Canada. Treisman, Daniel. (1998), “Decentralization and Inflation in Developed and Developing Countries”, Mimeo, Department of Political Science, UCLA. 82 PERANAN KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Iskandar Simorangkir1 Abstrak Perdebatan hubungan kebijakan moneter dan fiskal terkait dengan dampak defisit anggaran yang dapat mengganggu inflasi yang merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Sebaliknya, bagi pembuat kebijakan fiskal inflasi yang terlalu ketat dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Tidak terdapatnya koordinasi diantara kedua kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi. Paper ini akan membahas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia dari tahun 1969 hingga tahun 2002 baik dengan analisis empiris dan menggunakan pendekatan game teori baik berupa cooperative dan non-cooperative game. Hasil analisis empiris dan simulasi teori permainan menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan mo1 Kepala Biro Riset Ekonomi, Bank Indonesia dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia. Email: [email protected] dan [email protected] . Penulis mengucapkan terimakasih kepada n peserta seminar call for papers PPSK-FE UI tahun 2005 83 neter dan fiscal memberikan kerugian output (output loss) yang lebih kecil dibandingkan jika kedua kebijakan tidak berkoordinasi. ************* Key words: Game Theory, Koordinasi, Kebijakan moneter dan fiskal JEL Classification: C71, C72, E63 1. Pendahuluan Pembahasan mengenai pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal telah lama menjadi topik perhatian dikalangan akademisi dan praktisi. Sebagian berpendapat bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi. Sebagian pandangan yang lain berpendapat bahwa sebaiknya kedua otoritas kebijakan tersebut tidak memperhatikan tingkah laku otoritas kebijakan yang lain karena dengan koordinasi tujuan kebijakan moneter dan fiskal tidak dapat dilakukan secara optimal. Perdebatan mengenai pentingnya koordinasi antar kebijakan moneter dan fiskal terkait dengan adanya perbedaan penekanan tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perbedaan penekanan pada kedua kebijakan tersebut dapat mengakibatkan hasil akhir kedua kebijakan tidak optimal bagi perekonomian. Pembiayaan fiskal defisit yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflation). Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari interaksi kebijakan moneter dan fiskal terhadap kinerja makroekonomi telah lama dibahas baik secara teoritis maupun empiris. Berbagai studi menunjukkan bahwa sinergi kebijakan moneter dan fiskal 84 akan mendorong tercapainya tujuan optimal (Oudiz dan Sachs, 1984). Sementara Rogoof dan Keanth (1985) mengemukakan bahwa hasil interaksi kebijakan moneter dan fiskal tergantung dari besarnya distorsi perekonomian. Semakin besar distorsi dalam perekonomian, maka semakin kecil hasil dari proses interaksi dari kedua kebijakan. Sebaliknya, kajian Beetsma dan Bovenberg (1998) menunjukkan bahwa tidak terdapat manfaat dari koordinasi kebijakan moneter dan fiskal jika terdapat pertentangan tujuan kedua kebijakan dan nominal upah telah ditetapkan. Terlepas masih adanya perbedaan pandangan tentang manfaat koordinasi, pengalaman empiris negara-negara di Amerika Latin pada akhir tahun 1980-an menunjukkan bahwa pembiayaan fiskal defisit yang besar dan terjadi terus menerus melalui penciptaan uang baru oleh bank sentral (quasi fiscal) telah mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami hiper inflasi dan resesi ekonomi yang dalam. Pengalaman Indonesia pada tahun 1960-an juga menunjukkan kejadian yang sama dan bahkan akibat tingginya laju inflasi uang rupiah dipotong (sanering) nilainya. Pengalaman beberapa negara termasuk Indonesia menyadarkan pembuat kebijakan untuk melakukan koordinasi. Koordinasi kedua kebijakan tersebut secara harmonis dapat meningkatkan social welfare masyarakat. Dengan koordinasi, defisit pengeluaran pemerintah dapat terkendali sehingga laju inflasi dapat dicapai pada tingkat yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat dicapai. Permasalahan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia menjadi lebih penting lagi sejak Bank Indonesia mengumumkan penerapan secara penuh kerangka kebijakan moneter inflation targeting (ITF). Tidak sedikit pengamat ekonomi berpendapat bahwa penerapan ITF yang terlalu kaku akan membahayakan kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang hanya memperhatikan target inflasi dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan pada lanjutannya akan meningkatkan pengangguran di Indonesia. Dengan demikian diperlukan adanya keseimbangan pencapaian tujuan dari masing-masing kebijakan (striking the balance) agar hasil yang dicapai menjadi optimal. 85 Sejalan dengan pemikiran di atas, paper ini akan membahas mengenai perkembangan dan dampak kooordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Setelah bagian pendahuluan ini, paper selanjutnya akan membahas perspektif teori kebijakan moneter dan fiskal serta dilanjutkan pembahasan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Bagian akhir ditutup dengan kesimpulan dan implikasi kebijakan dari temuan di dalam pembahasan. 2. Perspektif Teoritis dan Empiris Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Perdebatan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari terdapat perbedaan penekanan dalam pencapaian tujuan masing-masing kebijakan. Tujuan utama kebijakan moneter lebih ditekankan pada stabilitas harga, dengan dasar beberapa pertimbangan. Pertama, dengan output ditentukan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang maka segala kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menciptakan inflasi (the short-run Phillips-curve) sehingga tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi riil (Kydland and Prescott, 1977). Kedua, rational economic agent mengerti bahwa tindakan kejutan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendorong inflasi dapat mendorong terjadinya permasalahan timeconsistency (Barro and Gordon, 1983). Ketiga, Kebijakan moneter mempengaruhi variabel ekonomi memakan waktu panjang dan mempunyai lag (Friedman, 1968). Keempat, kestabilan harga dapat mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih baik karena akan mengurangi biaya yang berasal dari inflasi. Penetapan stabilitas harga sebagaimana dikemukakan di atas akan mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun di sisi lain jika pencapaian kebijakan moneter tidak dilakukan secara terukur juga dapat mengakibatkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat menekan (sequeze) pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran. 86 Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Kebijakan fiskal yang terlalu longgar dalam pencapaian tujuan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat (Traclet, 2004). Pertama, Fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding-out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Pengalaman empiris di negara-negara Amerika Latin, negara Afrika dan negara mantan eropa timur pada tahun 1988-1991 menunjukkan bahwa fiskal defisit yang kronis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya hyper-inflation di negara-negara tersebut. Defisit fiskal yang dibiayai dari penciptaan uang telah mengakibatkan pesatnya pertumbuhan uang beredar dan selanjutnya hal tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi di negara-negara tersebut. Pada tabel 1 terlihat fiskal defisit pemerintah Peru telah mengakibat+kan peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1.052,6% per tahun pada periode tahun 1988-1991. Pesatnya pertumbuhan uang beredar tersebut tanpa diikuti peningkatan produksi merupakan penyebab melesatnya laju inflasi di negara tersebut hingga mencapai 1.694,3%. Hiper inflasi telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga negara tersebut jatuh ke dalam resesi ekonomi. Pengalaman negara-negara Afrika, beberapa negara Eropa dan negaranegara Amerika Latin lainnya mengikuti pola yang sama, yaitu fiskal defisit telah mengakibatkan tingginya uang beredar dan hiper inflasi. 87 Tabel 1. Pertumbuhan Uang Beredar dan Laju Inflasi di Beberapa Negara (1988-1991) Beberapa data empiris di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang longgar dengan kebijakan moneter yang longgar melalui penciptaan uang baru untuk pembiayaan defisit dapat mengakibatkan terjadinya hiper inflasi dan gangguan stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan beberapa fakta tersebut maka diperlukan koordinasi kedua kebijakan tersebut. Beberapa penelitian empris telah dilakukan untuk mengetahui dampak dari koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian. Pendekatan populer yang sering digunakan adalah pendekatan teori permainan (game theory) untuk mengetahui ketiadaan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Secara teoritis, terdapat empat jenis hasil yang didapatkan dari kebijakan bauran (policy mix) dari kebijakan moneter dan fiskal jika keputusan dilakukan secara bebas satu dengan lainnya (independent), yaitu: 1. 2. 3. 4. 88 Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat Hasil dari keempat bauran kebijakan (policy mix)tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2. Bauran Kebijakan (Policy mix) Moneter dan Fiskal .HELMDNDQ0RQHWHU/RQJ JDU .HELMDNDQ0RQHWHU.HWDW .HELMDNDQ)LVNDO /RQJJDU +DVLO(IHNWLI +DVLO6DOLQJ0H QLDGDNDQ .HELMDNDQ)LVNDO.HWDW +DVLO6DOLQJ0HQLDGDNDQ +DVLO(IHNWLI Dampak dari bauran kedua kebijakan dapat dijelaskan dalam kerangka IS/LM sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1, 2, 3 dan 4 di bawah ini. 89 Berdasarkan kerangka IS/LM tersebut di atas, bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang longgar akan mendapatkan manfaat terbesar jika perekonomian suatu negara mengalami resesi, seperti ditunjukkan oleh gambar 1. Dengan kebijakan moneter dan fiskal yang longgar yang dilakukan bersamaan, maka output (y) akan meningkat dari y0 ke y1 dengan beban peningkatan suku bunga dari ro ke r1. Pada masa inflasi yang tinggi (hyper inflation), bauran kebijakan moneter dan fiskal yang ketat yang dilakukan secara bersamaan akan lebih efektif karena dapat mengurangi positive output gap dan pada lanjutannya akan mengurangi laju inflasi, seperti ditunjukkan pada gambar 4. Sementara itu, jika bauran kebijakan adalah kebijakan moneter longgar dan kebijakan fiskal ketat atau kebijakan moneter ketat dan kebijakan fiskal longgar, maka dampak kedua kebijakan tersebut terhadap ouput saling meniadakan. Pada gambar 2, kebijakan moneter yang longgar akan meningkatkan ouput, sementara kebijakan fiskal yang ketat akan mengurangi output sehingga sehingga dampak kedua bauran kebijakan tersebut menjadi kurang efektif2. Gambar 3 juga menunjukkan pola yang sama, kebijakan moneter yang ketat akan mengurangi output dan kebijakan fiskal akan meningkatkan output sehingga kedua kebijakan kurang efektif dalam meningkatkan output. Bauran kebijakan dalam kerangka IS-LM di dasarkan atas masih belum mempertimbangkan peranan koordinasi sehingga masing-masing bertindak independent. Untuk melihat lebih jauh dampak dari koordinasi keuda kebijakan terhadap kinerja makroekonomi maka akan digunakan pendekatan teori permainan (game theory). Untuk mengenal lebih jauh tentang pendekatan game theory dalam menganalisa efek ketiadaan koordinasi kebijakan pada kondisi makroekonomi, penulis membuat suatu monetary-fiscal game lengkap dengan hasil yang akan didapatkan dan kerugian yang haris dibayar oleh masing-masing otoritas, seperti ditunjukan oleh gambar di bawah ini (Bennett dan Loayza, 2002): 2 90 Pada gambar 2 dan 3, magnitude dari kedua kebijakan diasumsikan sama sehingga output tetap. Pada dasarnya besar kecilnya output yang dihasilkan dari bauran kedua kebijakan sangat tergantung dari magnitude kedua kebijakan, tetapi kedua kebijakan saling meniadakan. Tabel 3 : A Monetary-Fiscal Game : Outcomes and Payoff Berdasarkan tabel 3 diatas, diasumsikan bahwa setiap otoritas kebijakan memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu: kebijakan pengetatan maupun kebijakan pelonggaran ( a tight or a loose policy ). Ketika keduanya bersamasama memilih kebijakan pengetatan maka akan menghasilkan keadaan perekonomian dimana tingkat inflasi cenderung rendah dan jumlah pekerja yang rendah atau pengangguran tinggi, sedangkan ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat kebijakan yang longgar maka mengakibatkan tingkat inflasi meningkat sedangkan angka pengangguran cenderung rendah. Sedangkan ketika salah satu otoritas kebijakan membuat kebijakan pengetatan sedangkan yang lain membuat kebijakan pelonggaran dan sebaliknya, maka tingkat pengangguran dan inflasi cenderung berada pada tingkat sedang. Nash Equilibrium pada game ini terdiri dari kebijakan moneter ketat dan kebijakan fiskal longgar. Jika kita melihat table Payoff schedule diatas, ternyata nilai payoff untuk kebijakan moneter ketat dan kebijakan fiscal longggar (yang juga merupakan solusi dari Nash Equilibrium) sama dengan 91 nilai payoff untuk kebijakan moneter longgar dan kebijakan fiscal ketat. Namun dalam jangka panjang, kombinasi kebijakan moneter longgar dan fiskal ketat lebih sehat daripada kebijakan moneter ketat dan fiskal longgar (Nash Equilibrium). Hal ini disebabkan kebijakan tersebut tidak berkompromi terhadap fiscal sustainability dan tidak memperlemah kapasitas investasi sektor swasta. Beberapa penelitian empiris telah dilakukan di beberapa negara untuk mengetahui dampak sinergi atau koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Penelitian empiris dengan menggunakan teori permainan yang dilakukan Petit (1989), Bannet dan Loayza (2002), Bartolomeo dan Gioacchino (2004), serta Faure (2004) menunjukkan bahwa koordinasi memberikan hasil yang lebih baik bagi perekonomian dibandingkan dengan hasil tidak terdapat koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sementara itu, pengujian model stochastic yang dilakukan oleh Friedman dan Benjamin (1979) dan Oudiz dan Sach (1984) menunjukkan bahwa sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi dibandingkan jika terdapat sinergi diantara kedua kebijakan tersebut. Sebaliknya, penelitian Beetsma dan Bovenberg (1998) menunjukkan bahwa koordinasi tidak akan memberikan hasil positif jika terdapat konflik target dari kedua kebijakan dan upah minimal telah ditetapkan di depan. Pada umumnya, hasil penilitian empiris menunjukkan bahwa koordinasi memberika manfaat yang lebih besar jika dilakukan koordinasi. 3. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia Keberhasilan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, fiskal, perdagangan dan Industri, dalam mencapai tujuan akhir tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan tanpa memperhatikan kebijakan di sektor lain akan tidak optimal dan bahkan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh kebijakan moneter yang hanya mengutamakan kestabilan harga atau inflasi yang 92 rendah dapat mengganggu tujuan kebijakan fiskal karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Dengan demikian peranan koordinasi menjadi penting dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan akhir daripada kebijakan ekonomi makro, berupa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kebijakan fiskal yang terlalu longgar sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang terlalu ketat, seperti penarikan pajak yang berlebihan di masyarakat dapat menurunkan konsumsi3 atau mengurangi alokasi dana yang produktif sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi. 3.1. Aspek Hukum Koordinasi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Secara hukum, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia mengalami masa pasang surut sejalan dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku. Pada masa Undang Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan anggota dewan moneter yang ketuanya adalah Menteri Keuangan dan merupakan perwakilan Pemerintah. Secara hukum, dengan kondisi tersebut tidak ada permasalahan koordinasi antara Pemerintah dan BI karena BI merupakan mitra kerja di dalam dewan moneter. Namun karena BI termasuk bagian dari Pemerintah, maka tidak terdapat lagi sistem pengendalian intern yang dapat mencegah Pemerintah untuk membiayai defisitnya berasal dari BI. Pada periode tersebut, tidak sedikit BI memberikan kredit kepada Pemerintah, lembaga pemerintah dan bank, seperti kredit kepada BULOG dan kredit likuiditas. Pemberian kredit tersebut merupakan penciptaan uang baru oleh BI yang bersifat inflationary sehingga dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. 3 Ricardian equivalence mengemukakan bahwa konsumsi tidak akan berubah karena pada masa yang akan datang masyarakat berekspektasi akan terjadi pemotongan pajak sehingga konsumsi tidak berubah. 93 Berdasarkan Undang Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun independen, dalam undang undang tersebut juga disebutkan beberapa pasal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, misalnya, dalam penjelasan pasal 10, dalam menetapkan sasaran inflasi, Pemerintah berkoordinasi dengan BI. Pasal 54 juga mengemukakan tentang koordinasi, yaitu terkait dengan kewajiban BI untuk memberikan pendapat dan pertimbangan permasalahan ekonomi serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Selain itu, pasal 55, ayat 1 juga menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dari sisi pandangan kebijakan moneter, pasal ini dapat diterjemahkan pembiayaan fiskal defisit harus memperhatikan tujuan akhir kebijakan moneter berupa stabilitas rupiah. Dalam ayat 4 pasal yang sama disebutkan BI dilarang membeli surat-surat utang negara di pasar primer. Pasal tersebut merupakan suatu upaya pencegahan agar pemerintah tidak membiayai fiskal defisit secara langsung dari bank sentral yang dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi. Berdasarkan Undang Undang Bank Indonesia terlihat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah diatur cukup baik, seperti terdapat pembatasan pembiayaan fiskal defisit yang berasal dari Bank Indonesia serta koordinasi penetapan sasaran laju inflasi. 3.2. Analisis Empiris Koordinasi kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia Pada bagian sebelumnya diuraikan hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal dari sisi aspek hukum. Pada bagian berikutnya akan diuraikan data-data empiris mengenai hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum masuk lebih jauh terhadap topik tersebut, secara singkat akan diuraikan mengenai masing-masing tujuan kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. 94 Seperti di negara-negara lainnya, tujuan kebijakan fiskal di Indonesia khususnya sejak PELITA I lebih ditekankan kepada mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dengan jalan memperluas kesempatan kerja. Seiring dengan meningkatnya pinjaman luar negeri, kebijakan fiskal juga diarahkan pada penyelesaian utang luar negeri dan dalam negeri untuk mecapai kondisi fiskal yang sutainable. Sementara itu, tujuan kebijakan moneter BI berdasarkan UU No. 23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2004 adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah tersebut mencakup inflasi dan nilai tukar rupiah. Pada masa sebelum UU tersebut dikeluarkan, tujuan BI selain menjaga kestabilan rupiah juga mencakup mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemberian kewenangan kepada BI hanya mestabilkan nilai rupiah agar BI lebih fokus dalam mencapai tujuannya dan sekaligus sebagai mengamankan atau mengendalikan kebijakan yang dapat membahayakan inflasi. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek melalui pembiayaan defisit dapat membahayakan inflasi dan stabilitas makro, dapat dinetralisir atau dikendalikan melalui kebijakan moneter yang ketat. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penekanan pada kedua kebijakan tersebut, yaitu kebijakan moneter lebih menekankan kepada inflasi, sementara kebijakan fiskal lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dengan adanya perbedaan penekanan tujuan tersebut maka jika tidak terdapat koordinasi maka dapat mengganggu stabilitas makroekonomi. Setelah membahas mengenai tujuan kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia serta terdapatnya perbedaan penekanan tujuan dari masingmasing kebijakan, pada bagian berikutnya akan dibahas fakta empiris koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Sebagaimana diketahui secara teoritis pertambahan uang primer4 (base money) akan sama 4 Uang primer adalah kewajiban moneter dari otoritas moneter (BI) yang terdiri dari uang kartal di masyarakat dan bank, giro bank di BI dan kewajiban sektor swasta lainnya. 95 dengan pertambahan net domestic assets (NDA) dan net foreign assets (NFA) atau net international reserve (NIR). Secara matematis perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 'M 0 'NDA 'NIR (1) 'M 0 adalah pertambahan uang primer, 'NDA terdiri dari pertambahan tagihan bersih kepada pemerintah (NCG), pertambahan tagihan bersih kepada bank, perorangan dan perusahaan (NCBS) dan pertambahan faktor-faktor lainnya (NOI). Setiap pengeluaran pemerintah akan dicatat di NCG sehingga jika tidak terjadi pengeluaran NCG maka uang primer (M0) akan meningkat. Berdasarkan data empiris seperti terlihat di grafik 1, Pertumbuhan Net Claim to Government ( NCG ) dengan pertumbuhan Base Money pada tahun 1981 sampai 2004 mempunyai kecenderungan untuk berhubungan positif, setiap terjadi ekspansi NCG, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan uang beredar. Hal ini dapat dilihat dalam plot grafik 1, pada saat terjadi ekspansi NCG pada tahun 1983 sebesar 31.81 % daripada tahun sebelumnya, menyebabkan pertumbuhan uang primer meningkat menjadi 25 % daripada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4 %. Pada tahun 1992 pertumbuhan NCG sebesar 27.45 % dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan NCG ini direspon positif oleh peningkatan uang primer pada saat itu yang pertumbuhannya meningkat sampai 31 % dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh pada tingkat 3 %. Respon positif terbesar uang primer terhadap perubahan NCG terjadi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998, pada saat itu pertumbuhan NCG meningkat menjadi 552 % dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 28 %, pertumbuhan NCG yang sangat besar tersebut menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan uang primer yang meningkat menjadi 77 % dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang berkisar pada tingkat 38 %. 96 Grafik 1. Pertumbuhan Tahunan NCG dengan Uang Primer Secara teoritis, melalui suatu proses penciptaan uang maka uang primer akan ditransformasikan ke dalam uang beredar dalam artian sempit (M1) dan dalam artian luas (M2). Pada saat pemerintah meningkatkan pengeluaran seperti tercermin dari peningkatan NCG, maka menyebabkan terjadinya peningkatan uang primer. Peningkatan uang primer akan berdampak pada peningkatan uang beredar ( M1/M2 ) seperti terlihat di grafik 2. Grafik 2. Pertumbuhan Tahunan Net Uang Primer dan M2 97 Sementara itu, berdasarkan grafik 3 terlihat bahwa hubungan antara uang beredar (M1/M2) dan inflasi adalah positif. Pada saat pertumbuhan uang beredar meningkat sampai 49 % pada tahun 1974, ternyata diikuti oleh peningkatan laju inflasi pada saat itu, yaitu sebesar 40%. Dampak positif pertumbuhan uang beredar juga dapat dilihat pada tahun 1980 dan tahun 1998, pada tahun-tahun tersebut pertumbuhan uang beredar mencapai 44 % dan 66 % sedangkan laju inflasi juga mengalami peningkatan sampai pada tingkat 18 % dan 58 %. Grafik 3. Pertumbuhan Uang Beredar dengan Tingkat Inflasi Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah (APBN) dan inflasi juga menunjukkan hubungan yang positif (Grafik 4). Pada saat pemerintah menetapkan kebijakan fiskal ekspansif maka akan menyebabkan peningkatan laju inflasi. Hal ini dapat dimengerti karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan agregat demand sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga secara umum (inflasi). Disaat pemerintah meningkatkan pengeluarannya pada tahun 1974 sampai 68,35 %, laju inflasi pada tahun tersebut juga meningkat menjadi 40 %. Peningkatan laju inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah juga terjadi pada tahun 1980, pada saat itu pertumbuhan pengeluaran pemerintah mencapai 48.6 % sedangkan laju inflasi mencapai 18 %. 98 Dampak positif pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap laju inflasi dapat dilihat juga tahun 1998 dan pada tahun 2000. Pada tahun 1998, ketika pertumbuhan pengeluaran pemerintah meningkat sampai 54 %, ternyata diikuti peningkatan laju inflasi sebesar 58 %, sedangkan pada saat pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurun sampai tingkat – 2 % pada tahun 2000, laju inflasi juga menurun sampai tingkat 3.7 %. Grafik 4. Pertumbuhan Pengeluaran APBN dengan Inflasi Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hubungan posistif. Dari grafik 5 dapat dilihat bahwa pengeluaran APBN cenderung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak positif paling nyata terlihat pada saat pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 12.5 % pada tahun 1994 daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5.3 %, pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar 7.5 % daripada tahun sebelumnya yang hanya 6.5 %. Pada saat krisis tahun 1998 hubungan tersebut tidak stabil, ketika pengeluaran pemerintah meningkat sampai 54.2% pada tahun 1998, ternyata pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut malah mengalami penurunan sampai tingkat – 13 %. 99 Grafik 5. Pertumbuhan Pengeluaran APBN dengan Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu, hubungan kebijakan moneter dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif Suku bunga deposito berjangka 3 bulan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat grafik 6. Dalam plot grafik 6 terlihat bahwa pada saat suku bunga berjangka 3 bulan meningkat, maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi pengalami kontraksi. Pada tahun 1980, saat suku bunga deposito diturunkan pada tingkat 6 %, maka pertumbuhan ekonomi pada saat itu meningkat sampai 9.8 %. Sedangkan pada saat bunga deposito ditingkatkan menjadi 18 % pada tahun 1985, membuat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. 100 Grafik 6. Suku Bunga dengan Pertumbuhan Ekonomi Pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiscal sebagaimana diuraikan dalam analisis grafis sebelumnya juga didukung penelitian Simorangkir (2005). Penelitian tersebut menggunakan model teori permainan (game theory) dengan menggunakan data dari tahun 19702004. Tujuan optimal dari masing-masing kebijakan moneter (BI) dan kebijakan fiskal (Pemerintah) ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, dilakukan simulasi seberapa besar kerugian output (output loss) jika masingmasing kebijakan hanya mementingkan tujuannya sendiri-sendiri dan jika bekerjasama atau berkoordinasi. Hasil dari output loss terhadap perekonomian jika BI dan pemerintah tidak bekerjasama berdasarkan teori permainan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 101 Tabel 3 Jumlah Kerugian Pemerintah Jika Pemerintah dan BI Tidak Bekerjasama Berdasarkan hasil perhitungan di atas terlihat, jumlah kerugian pemerintah terhadap ekonomi jika pemerintah (kebijakan fiskal) dan BI (kebijakan moneter) tidak bekerjasama adalah sebesar 17,95. Selanjutnya, jika pemerintah berkeinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar (seperti tercermin dari bobot GDP dan G yang lebih besar) maka jumlah kerugian bagi perekonomian menjadi lebih besar, yaitu sebesar 18,60. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi lebih kecil atau inflasi lebih rendah maka jumlah kerugian bagi ekonomi yang berasal dari pemerintah menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 17,30. Dengan mengacu pada hasil empiris tersebut, maka setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek mengakibatkan social welfare menjadi berkurang. Total kerugian ekonomi yang berasal dari BI jika pemerintah dan BI tidak bekerjasama adalah sebesar 16,36. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa jika BI terlalu memperhatikan inflasi dan mengabaikan pertumbuhan 102 ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya total kerugian ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut tercermin dari tabel 3 yang menunjukkan bahwa social lost ekonomi lebih besar (17,22) jika BI ingin menurunkan inflasi yang lebih rendah dari path idealnya. Sebaliknya, jika kebijakan moneter lebih diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitasnya maka social lost ekonomi menjadi lebih kecil. Tabel 4. Jumlah Kerugian BI Jika Pemerintah dan BI Tidak Bekerjasama Sementara itu, jika kebijakan moneter (BI) dan kebijakan fiskal (Pemerintah) bekerjasama maka social lost ekonomi menjadi lebih kecil. Tabel 4 menunjukkan bahwa jika toleransi antar kebijakan sama (koefisien kerjasama sebesar 0,5) maka total social lost bagi perekonomian hanya sebesar 18,24 jauh di bawah total social lost jika tidak bekerjasama, yaitu sebesar 34,31. 103 Tabel 5 Total Kerugian Ekonomi Jika Bekerjasama 4. Tantangan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia Beberapa fakta empiris dan hasil studi seperti diuraikan sebelumnya menunjukkan betapa berbahayanya jika kedua kebijakan hanya mengutamakan tujuan masing-masing tanpa memperhatikan tujuan ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang berorientasi jangka pendek dalam mengejar pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan lemahnya stabilitas makroekonomi sehingga mendorong terjadinya overheating economy. Tingginya laju inflasi mendorong ketidakpastian ekonomi sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pengalaman krisis tahun 1997/1998 menyadarkan kembali tentang pentingnya orientasi kebijakan yang lebih berjangka panjang. Untuk 104 mengarahkan kedua kebijakan tersebut diperlukan orientasi baru dari kebijakan moneter dan fiskal. Orientasi baru tersebut diarahkan kepada konvengensi tujuan dari kedua kebijakan, yaitu memperoleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara kelambagaan untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat kecenderungan secara global untuk menggunakan rules dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal dibandingkan dengan discretion. Kecenderungan tersebut juga terjadi di Indonesia, sejak Juli 2005 BI telah menerapkan inflation targeting framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneternya. Dalam ITF, BI mempunyai tujuan untuk mencapai inflasi yang rendah sesuai kapasitas ekonomi serta menggunakan suku bunga (BI rate) sebagai signal kebijakan moneter. Di sisi yang lain, Pemerintah menggunakan besarnya budget defisit sebagai rules dalam pelaksanaan kebijakan fiskalnya sejak era reformasi. Penerapan kedua kebijakan tersebut secara harmonis tidaklah mudah karena masih banyaknya tantangan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada dua tahun terakhir (5,1% pada tahun 2004 dan 5,6% pada tahun 2005) tidak mampu menutupi peningkatan angkatan sehingga pengangguran meningkat dari sebesar 9,5% pada tahun 2003 menjadi 9,9% dan 10,3% masing-masing pada tahun 2004 dan 2005. Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), pemerintah juga telah menetapkan target fiskal defisit masing-masing sebesar -0,7% pada tahun 2005 dan secara berangsur-angsur defisit akan dikurangi sehingga pada tahun 2008 akan mengalami balanced budget dan tahun 2009 mengalami surplus sebesar 0,3%. Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, target inflasi telah ditetapkan masing-masing sebesar 5,5% pada tahun 2005 dan 5% pada tahun 2007. Data di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal akan mengarah ke balance budget dan bahkan menunjukkan surplus, sementara di sisi lain sumber-sumber pendorong pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Investasi yang diharapkan menjadi sumber penggerak roda ekonomi masih sangat terbatas. Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi yang 105 dalam jangka panjang tidak sustainable. Terbatasnya sumber pertumbuhan ekonomi, dapat mendorong kebijakan fiskal untuk melakukan kebijakan discretion karena kuatnya tekanan dari masyarakat khususnya tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan lain yang tidak kalah beratnya adalah peningkatan harga minyak dunia. Kecenderungan harga minyak dunia di tengah terbatasnya sumber penerimaan pemerintah untuk menutupi bahan bakar minyak (BBM) akan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan harga minyak di dalam negeri pada masa-masa mendatang. Peningkatan harga BBM akan mendorong peningkatan laju inflasi dan pada lanjutannya meningkatkan resiko usaha. Dari sisi kebijakan moneter, peningkatan laju inflasi akan mendorong BI untuk melakukan respon pengetatan kebijakan moneter jika ekspektasi masyarakat meningkat. Banyaknya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional dapat menghambat harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat mendorong pemerintah melakan kebijakan fiskal discretionary dan pada lanjutannya akan mendorong peningkatan laju inflasi. Sementara itu, kebijakan moneter yang terlalu ketat dalam rangka memerangi inflasi dapat mendorong perekonomian ke resesi yang dalam. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ada keseimbangan antara tujuan kebijakan moneter dan fiskal (striking the balance) dengan melihat kapasitas ekonomi. 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan D Pengalaman empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa pembiayaan fiskal defisit yang berasal dari bank sentral dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan laju inflasi dan instabilitas makroekonomi. E Secara hukum koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia telah berjalan baik, beberapa pasal di dalam Undang Undang Bank Indonesia telah secara tegas mengatur koordinasi kebijakan moneter dan fiskal khususnya yang terkait dengan inflasi 106 sebagai tujuan kebijakan moneter dan permasalahan ekonomi dan APBN. F Kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif atau mengutamakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mengakibatkan social lost yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Demikian juga halnya dengan kebijakan moneter yang terlalu ketat atau mengutamakan inflasi tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan social lost yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. G Koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memberikan social lost yang lebih kecil terhadap perekonomian dibandingkan jika tidak berkoordinasi. H Banyaknya permasalahan perekonomian nasional saat ini, seperti tingginya pengangguran dan kemiskinan, berpotensi mengganggu koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Keinginan pemerintah untuk memerangi pengangguran dapat mengakibatkan kebijakan fiskal terlalu ekspansif sehingga dapat meningkatkan inflasi yang merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Sejalan dengan tantangan tersebut, maka diperlukan memelihara keseimbangan antara tujuan kebijakan moneter dan fiskal (striking the balance) yang sesuai dengan kapasitas perekonomian. I Implikasi kebijakan dari temuan tersebut adalah diperlukan koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang lebih erat lagi, seperti mempertahankan dan meningkatkan peran tim koordinasi BI dan Departemen Keuangan, serta mengembangkan tim koordinasi tersebut hingga ke daerah-daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah. 107 Daftar Kepustakaan Abel, Andrew B. And Ben S. Bernanke. Macroeconomics, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Co., 1995. Ali, Faizul Ariff and T.K. Jayaraman. “Monetary and Fiscal Policy Co-ordination in Fiji“. Working Paper 2001/01, May 2001. Bartolomeo, Giovanni Di and Debora Di Gioacchino. “Fiscal-Monetary Policy Coordination and Debt Management: A Two Stage Dynamic Analysis”. Working Paper No. 74, Universita Degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartiento di Economia Pubblica, 2004. Beetsma, Roel M.W.J. and A.L. Boveberg, 1998. Monetary Union Without Fiscal Coordination May Discipline Policy Makers. Journal International Economy, 45: 239-258. Bennet, Herman dan Norman Loayza. “Policy Biases When The Monetary and Fiscal Authorities Have Different Objectives”. Dalam buku Monetary policy: Rules and Transmission Mechanism, edited by Norman Loayza and Klaus Schmidt-Hebbel, Santago, Chile, 2002, Central Bank of Chile. Faure, Pierre. “Monetary and Fiscal Policy Games and Consequences of Organisational Differences between the European Unio and The Rest of the World”. Working Paper Universite Paris XII (Val-deMarne), et CEFI, 2002. Friedman, M. And M. Benjamin, 1970. Even the St. Louis Equation Now Believe in Fiscal Policy. Journal Money, Credit and Banking, 9: 2542. Javed, Zahoor Hussain and Ahmet Sahinoz. “Interaction of Monetary and Fiscal policy in Case of Turkey”. Journal of Applied Science, Asian Network for Scientific Information: 2005. Labertini, Luca and Ricardo Rovelli. “Optimal Fiscal Stabilization with Credible Central Bank Independence”. Working Paper, Department of Economics, University of Bologna, December 21, 2002. 108 Petit, Maria Luisa. “Fiscal and Monetary Policy Co-Ordination: A Differential Game Approach”. Journal of Applied Econometrics, Vol. 4, No. 2 (Apr-Jun., 1989). Rothenberg, Alexander D. “The Monetary-Fiscal Policy Mix: Empirical Analysis and Theoretical Implications”. Working Paper, mimeo, 2004. Simorangkir, Iskandar. “Koordinasi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Suatu Pendekatan dengan Game Theory”. PPSK Bank Indonesia Working Paper, 2005. Traclet, Virginie. “Monetary and Fiscal Policies in Canada: Some Interesting Principles for EMU?”. Working Paper 2004-28, Bank of Cananda. 109 110 FISCAL AND MONETARY POLICY INTERACTION: EVIDENCES AND IMPLICATION FOR INFLATION TARGETING IN INDONESIA Firman Mochtar1 Abstract The paper examines fiscal and monetary policy interaction in Indonesia prior and post economic crises 1997,by estimating quasi fiscal activities of the central bank (QFA) and also by assessing fiscal versus monetary dominance aspect. The paper finds that economic crises 1997 generated QFA in Indonesia. Confirming the QFA evidence, further test also indicates fiscal policy played a dominance role post 1997, though it can be classified in weak form. These evidences lead to the policy implication that monetary policy in Indonesia still call for a higher fiscal discipline and commitment to maintain the sustainability. The failure to solve fiscal performance optimally could deteriorate monetary policy effectiveness to control inflation under inflation targeting framework. 1. Introduction Intensive challenges in conducting macroeconomic policies emerged in Indonesia since the Asian crises hit in 1997. Monetary policy was 1 Economist at Bank Indonesia. Email address: fi[email protected] 111 engaged with exhaustive challenges. Exchange rate depreciated sharply while monetary base grew rapidly triggered by central bank’s liquidity support. Under these circumstances, inflation increased sharply in 1998 to reach 82%. On fiscal policy side, the sharp depreciation of the exchange rate inevitably raised the foreign debt burden in term of domestic currency. Moreover, a huge amount of expenditure was still required regarding the policy to restore the banking system and also to finance other government operational expenditures. Macroeconomic policies pursued afterwards expressed the effort to solve the problem. Tight monetary policy was conducted to absorb a huge amount of excess liquidity. From fiscal side, central government had issued domestic debt both for replacing the central bank’s liquidity support and for recapitalizing banking system during period September 1998 and October 2000 (Bank Indonesia, 1999 and Hawkin, 1999). Furthermore, starting 2002 government also issued different types of bond to finance the state budget deficit2. The total government debt, both domestic and external, rose from 25% of GDP at end-1996 to 96% at the end of 2000. The paper is intended to test empirically fiscal and monetary policy interaction during that period of macroeconomic adjustment 1998-2003. The interaction will be viewed from the plausibility of quasi fiscal activities by central bank (QFA)3 and be extended to test fiscal versus monetary dominance. The QFA estimation is motivated by the fact that during the period adjustment, the fiscal side come under a heavy burden while in monetary side accorded a sharp increase of central bank balance sheet. On assumption that consolidated government budget identity holds, this fact generates some suspicion of fiscal monetization in Indonesia during that period. Conceptually, this circumstance could lead to QFA since QFA emerges if total public sector spending is above additional central 2 Boediono (2004) explained that the increase of the domestic debt was associated with the effort to support banking system and classified them into three main policy namely (i) policy to overcome the shortage of liquidity in banking system through Bank Indonesia’s liquidity support, (ii) policy to guarantee public’s deposit in banking system and (iii) policy to recapitalize banking system. 3. The acronym QFA will be used frequently to express the quasi fiscal activities by central bank 112 government public debt.As residual of those two variables, QFA is required to finance the central government financial gap. Moving forward from QFA issue, fiscal versus monetary dominance test is also gauged to confirm the QFA result. Still on assumption that consolidated government budget identity holds, the presence of QFA could also imply the presence of the fiscal dominance in view of fiscal and monetary policy interaction. Under this circumstance, fiscal policy which is reflected in present value of primary balance will move exogenously to the initial total public debt and sequentially required monetary policy to satisfy consolidated budget identity. Extending method proposed by Buiter (1993), Budina-Wijnbergen (2000) and Markiewicz (2001) for the QFA estimation, the paper finds that fiscal and monetary interaction in Indonesia during the crisis 1997/98has created QFA phenomenon. Most of the source behind the figure since 1998 inevitably was the effect of rescue operation held by the central bank associated with the financial system. In addition to this source, huge increase in central bank securities also contribute to QFA because it has enlarged the cost of central bank on monetary instrument and together with the first source has sequentially worsen central bank balance sheet position. Parallel to the QFA result, the paper also finds that fiscal policy is likely to be more dominant in view of fiscal and monetary policy interaction during the crises. Utilizing method employed by Canzoneri et.al(2001) and Tanner and Ramos (2002), paper obtains that fiscal policy has moved exogenously to debt performance post 1997 such that could lead to the emergence of fiscal dominance classification. Based on the findings, the paper finds some implication for monetary policy in Indonesia. The nature of fiscal and monetary policy interaction implies that imposing monetary policy effectiveness in Indonesiastill call fora higher fiscal discipline and commitment of the government to maintain the sustainability. Parallel to some arguments4, thispaper’s results implythe failure to solve fiscal performance optimally could deteriorate 4. See Loyo (1999), Blanchard (2004), Favero and Giavazzi (2004) 113 monetary policy effectiveness to control inflation under inflation targeting framework (ITF). Paper will be organized into five parts. Part two estimates the QFA by central bank in Indonesia. Employing part two result, part three presents the test of fiscal versus monetary policy dominance. Part four addresses implications of the results for the effectiveness of monetary policy in Indonesia under ITF. Part five concludes the paper. 2. Estimating Quasi Fiscal Activities by Central Bank Indeed, the estimation of QFA will only provide an approximation, not a precise number because the method used to estimate only applies to the aggregation level. However, the approach in this paper still provides a good direction of QFA if the precise information of QFA is not available (Markiewicz, 2001). QFA is obtained from the simple manipulation of consolidated government budget constraint which is formed from central government budget and central bank financial account. As explained in many macroeconomic and monetary theory text books5, consolidated government budget constraint defines that in addition to revenue from tax, government should sells bonds to public and/or to the central bankto meet the spending.Parallel to this basic concept and on assumption that consolidated government budget identity holds, QFA will be acquired if total public sector borrowingrequirement6 is higher than additional central government public debt which eventually finance from central bank to fill central government financial gap. 2.1 A Brief Conceptual of QFA To describe the QFA in Indonesia, I modified and extended the Buiter (1993), Budina-Wijnbergen (2000) and Markiewicz (2001) analytical framework such that it could represent Indonesia’s consolidated public 5. See Walsh (2003, chapter 4) for the an example 6. which is also called overall budget balance obtained from tax revenue minus total government spending 114 budget identity ‘prototype’. After having some simple algebra manipulation from central government budget and central bank financial account, QFA analysis will focus on the term NOI in following equation7: (1) 'DCg - 'DEPg - 'Bm + E-1 ('NFA*) - 'M + 'Cp = 'NOI where CDg - credit to government from central bank, DEPg - government deposits at the central bank, Bm - central bank securities used as monetary instrument, E – nominal exchange rate, NFA – net foreign asset, M – monetary base,and Cp - credit to non-governmental sector (commercial bank and private sector). The asterisk * denotes variable in foreign currency, while ' indicates the absolute change in the expression that follows. Equation (1) is the centre of analysis of the QFA which describes the amount of money required by the central bank to balance the fiscal operation by central government such that can satisfy the consolidated government budget constraint between central government budget and central bank financial account. Equation (1) implies the amount of money created by central bank as part of public entities to finance the central government spending. By definition, indeed equation (1) indirectly also reflects the flows of central bank’s net worth for a certain period because it also shows the difference between bank’s asset and its liabilities8. The negative value of NOI could reflect that liabilities of the bank has exceeded asset and could indirectly provide the fragility of the central bank’s financial position. With respect to our case, the negative value of NOI could indicate a QFA by central bank at that period. One of the sources of the deficit in equation (1) is a higher of 'M. This equation implied that any shock that could rise 'M and subsequently will lead a deficit in QFA. Following Mackenzie and Stella (1996), the source of 'M risecould be initiated from the central bank rescue operation 7. For the detail algebra manipulation, see the original paper. 8 Stella (1997) distinguished definition between net worth and capital in view of central bank balance sheet. He defined net worth as the price a fully informed risk neutral investor would pay to purchase the bank under normal condition. Meanwhile capital was defined as the amount directly invested by shareholder plus accumulated retained earning minus losses. The term of net worth is more appropriate to our paper because it captures the changes in the value assets and liabilities both for past and future changes. 115 related to the financial system which can take a variety of form – from a simple infusion of capital, to an assumption of nonperforming loans, to an after-the-fact exchange rate guarantee. Table 1 reproduceMackenzie and Stella (1996) classification. Table 1 Classification of Quasi Fiscal Activities Operation Related to the Excahnge Rate System Multiple exchange rate Import deposits Deposit on foreign assets purchases Exchange rate guarantees Subsidized exchange risk insurance Operation Related to the Financial System Subsidized Lending Administered lending Preferential rediscounting practices Poorly rediscounting practices Loan guarantees Reserve requirements Credit ceiling Rescue operations Source: Mackenzie and Stella (1996), page 4 Further discussion could be addressed to the role of central bank securities ('Bm) in estimatingthe QFA. By definition equation (1) implied that sterilization by central bank through increasing 'Bm implies will raise QFA. Nevertheless, by practice this hypothesis could not be always occurred because when base money ('M) would also contract the same amount when central bank sterilize the money supply by selling the central bank securities. The higher 'Bm would raise the QFA only if 'M does not changedue to other source of monetary policy expansion which is higher that central bank policy contraction through the central banksecurities. The Argentina’s experience in 1989-1990 referred by Rodriguez (1994) and Beckerman (1995) could be parallel to this hypothesis because tight 116 monetary policy employed central bank securities caused a monetization and could not be fully sterilized by central bank. 2.2 Empirical Result: the crises triggered the central bank to run quasi fiscal deficits Employing the ratio to GDP for each variable of annual data 1986 – 2003, the empirical result of equation (1) indicates that banking crises played a big role in raising central bank’s QFA. The central bank has been running QFA since 1997 which reached the highest level in 1999. These figures were really different from pre-1997 environment which posed mostly neutral position in term of QFA. In comparing to primary balance of the central governmentreported by the central government, this QFA figure deviated in a wide range because central government primary balance during that period always showed a surplus number (Graph 1). From QFA and primary balance figures deviation, an interesting characteristic of those deviations between NOI and the government primary balance is the emergence of three different regimes of the fiscal adjustment and monetary movement. The first regimes prior 1990 which provide deficit number in central government primary balance and a relatively neutral in central bank operation. The second regime refers to the period between 1990 and 1997 which describes fiscal adjustment to maintain primary surplus while the central bank maintained a neutral position. The last regime is period after 1997 which engages deficits in central bank quasi-fiscal activities while primary balanceturned positive. 117 Graph 1 Quasi Fiscal Activities by Central Bank, Seigniorage, Government Primary and Overall Balance (% GDP) Source: Bank Indonesia, Ministry of Finance, author’s calculation Several facts explain the three different regimes. In first regime (i.e prior 1990), the deficit figures in government spending notably relates to the role of the government as the economic agent to enhance economic growth. To support the objective, the government used foreign debt as the financing source of deficit. This was possible because under small contribution of the private agent, government placeditself in the centre of economic development. From QFA analysis, several positive NOI implies that not all the foreign debt was spent into domestic economy. Instead, some of them were placed as deposit in the central bank account. The government account and NFA of central bank increased steadily in this period. In monetary policy part, this figure also represents the central bank role to sterilize government expenditure. Nevertheless, the figure in this regime could also lead a misleading interpretation because in this episode the lack of transparency in fiscal policy has a strong environment. During this time, the use of off-budget account also appeared in other financial institution. Therefore the deficit primary budget balance number can be misleading figures of central government operation during this regime. 118 From the second regime(1990 – 1997), the positive primary surplus of central government budget corresponds to higher revenue from the positive impact of high economic growth and high oil and gas price. Except in 1992, this economic environment leads the fiscal policy to accumulate surplus on both primary and overall balance. In result of the accumulated primary surplus and the high economic growth, fiscal sustainability tend to emerge described from declining trend of debt to GDP ratio (Graph 2). From monetary movement, it is again slightly neutral. Nevertheless some events still occurred at which contribute to QFA. As stipulated in central bank law 1968 act, the central bank should support government effort to enhanced economic growth and create employment. One policy of central bank related to the QFA in this regime corresponded to the activities of central bank credit to finance the private sector through liquidity credit of Bank Indonesia, so called KLBI. Before 1998, this credit posed a high number (Graph 3). Mackenzie and Stella (1996) argued this type of financing can be classified into QFA because it was formed as subsidized lending ranging from relative direct practice of lending at administered rates set below market, lending to poor credit risk and lending without adequate collateral. 119 Graph 2 Government Foreign and Domestic Debt (% GDP) Source: Bank Indonesia, Ministry of Finance, author’s calculation Graph 3 Bank Indonesia Liquidity Credit Source: Bank Indonesia, author’s calculation 120 Another item contributed to the QFA in this region relates to the managed floating exchange rate regime adopting during this period. Following Mackenzie and Stella (1996) classification, operation to exchange rate system can be classified into QFA by central bank because it both provide a hidden subsidy to the market that should paid by the central bank by maintaining the level of the exchange rate at certain range. Central banks in this period pursued sterilization policy of capital inflow in foreign exchange market such that could prevent the further domestic currency appreciation at that time (Graph 4). Hence, this managed floating exchange rate system inevitably reduces the central bank reserve and bring down the QFA level lower than the government primary balance. Graph 4 Rupiah Exchange Rate 1995 – 1997: Intervention Band and Actual Rate (Rp/USD) Source: Bank Indonesia The third regime was occurred since the Asia financial crises hit. The issue emerged in this region is apparently loose monetary policy 121 stance as reflected by the deficit number in NOI while fiscal stance keep trying to maintain government primary surplus balance. In the fiscal side performance, the primary balance indeed still reflects a government idea to keep concerning to debt sustainability. The sharp depreciation of Indonesia’s exchange rate lead an increase in foreign government debt in term of domestic currency (Graph 2). Unavoidably, this problem cause higher principal and interest repayment debt that ultimately cause deficit in overall balance. This unfortunate debt burden performance has both limited the government stimuli to the economy and restricted financing to restore the banking system. Fiscal problem had forced the government to issue the domestic debt. From September 1998 to October 2000, government issued two different domestic bonds i.e. bonds to replace the central bank’s liquidity support9 and bonds to recapitalize the banking system (Bank Indonesia, 1999 and Hawkin, 1999). In addition, starting 2002 government also issued domestic bond through market auction to finance the government budget deficit. This additional debt consequently brought to the higher burden of interest debt repayment than primary surplus obtained which reached the peak on 2000 (Graph 2). Interesting figures emerge since 1998 from the monetary side. Two type of analysis of equation (1) employed current exchange rate and constant exchange rate generally indicated that in this regime central bank run a high quasi fiscal deficit. The difference between current exchange rate result and 1997 constant exchange result is only in the year of 1998 which obtained a surplus number for the NOI. However, this figure could bring a misleading interpretation because those are more affected by the sharp depreciation effect of the exchange rate such that could raise the net foreign assets (NFA) in term of domestic currency value. To have a fair judgment then we should focus on the changes of the stock of the net foreign asset instead of the effect of exchange rate changes. Therefore, the rest of analysis, we will focus on 1997 constant exchange rate. 9 These liquidity support were issued to prevent bank run and payment system failure 122 The general justification of this post 1997 performance was the effect of rescue operation held by the central bank associated with the financial system. In 1998 central bank engaged deficit of NOI amounted -4.7% of GDP while in 1999 deficit was apparently getting higher. Those figures were contributed from liquidity support from central bank as lender of the last resort (Bank Indonesia, 1998, 1999). Mackenzie and Stella (1996) survey in some developing countries showed the possibility of the similar rescue operation could generate QFA were mostly contributed from an infusion of capital to a troubled institution, an assumption of non-performing loans, or an exchange rate guarantees by the central bank. Those sources of QFA probably existed in Indonesia while the crises occurred. In addition, some aspect in the central bank operation also contributes the deficit. Following equation (1), the positive central bank securities could also contribute to the deficit QFA. Following Mackenzie and Stella (1996) argument, increase of open market operation to sterilize the liquidity injection of the financial rescue operation could be classified to QFA because this central bank open market operation will enlarge the cost of central bank. Similar arguments were also proposed by Rodriguez (1994) and Beckerman (1995) for the case of Argentinan in 1989-90. For Indonesia case, this relates to the sharp increase of central bank securities (SBI) as shown since 1998 and subsequently has generate higher cost for monetary expenses of the central bank (Graph 5). 123 Graph 5 Central Bank Securities: Stock, Interest Rate and Monetary Operation Expenses Source: Bank Indonesia’s annual report 3. Test of Fiscal versus Monetary Dominance Part two results emphasize Mackenzie and Stella (1996) argument that central bank can affect the overall public sector balance without affecting the surplus in government primary balance. Description in regime three of Indonesia fiscal adjustment and monetary movement justify this argument by showing that the central bank has supported the consolidated government financing. This fact is indicated from deficit figures of NOI while primary balance still obtained surplus. These results lead a further question whether the sequential government primary surplus sufficiently expresses fiscal commitment and discipline regarding to debt performance and can be classified into monetary dominance in term of fiscal and monetary interaction sense. 124 3.1. Technical Approach To answer these questions, the study will be extended to investigate the fiscal versus monetary dominance in view of macroeconomic policy coordination. In this test, if government does not adjust the primary balance sufficiently to reach sustainable debt level while the central bank is forced to drive up the debt, then such regime will be classified into fiscal dominant regime. By contrast, if the government could always ensure the primary balance to balance inter-temporal budget in balance while monetary policy is set independently, then the economy is under monetary dominant (MD)10. As we will in the next section, the answer of this question will have some further implication to the monetary independence to maintain the price stability. This test basically is also initiated from the public sector budget oneperiod identity as used in the previous part. In short, the model will test the following analytical equation11: (2) where as the net government primary balance that has involved seignoirage, 'M=St as the nominal value of seigniorage, i as nominal interest rate and . The small case letters express the scaling of the respected variable to nominal GDP. Equation (2) describes that government should react negatively to the current outstanding government liabilities. The higher government debt liabilities should lead the lower present value of primary deficit decrease (ie. the government should run a primary surplus in the present value). By definition, this equation implies that primary balance surplus can be generated through adjustment in expenditures, taxes or seigniorage. To test empirically the existence fiscal or monetary dominance, equation (2) will be applied into Vector Autoregressive (VAR) method 10 The distinction between MD and FD regimes is due to Sargent and Wallace (1981) 11 See the original paper for detail derivation to obtain equation (2) 125 which is similar to Canzoneri et.al (2001) and Tanner and Ramos (2002)12. Before applying into VAR method, following Tanner and Ramos (2002), equation (2) should be manipulated into changes form. To obtain this, add the net government primary balance from both side of equation (2). Because represent the additional liabilities ( L ) required to finance the operational deficit then (2) is re-written in equation (3) which will be the focus of empirical test using VAR method. (3) To interpret VAR result which estimates in both directions of the variables of equation (3), then the interpretation of checking fiscal or monetary dominance should be treated in similar way. Following Tanner and Ramos (2002), first consider the effect of additional debt (adlt) innovation to future primary balance (pbt+1). The equation (2) interpret that the fiscal dominance (FD) will exist under this type of shock if primary balance are determined exogenously and unrelated to the level of previous additional debt and therefore the nominal and or discount factor must adjust in equilibrium to satisfy the equation. In addition, Tanner and Ramos (2002) also argue that the positive relationship could also indicate FD because it reflects that the primary deficits respond to liabilities in unstable fashion. On contrast, monetary dominance (MD) exist in this type of shock if primary balance is determined in such way that equation (2) is always satisfied, regardless the nominal income and discount factor behave. According to this interpretation and equation (2), the relationship between primary balance and the additional government liabilities should be negative and significant because they indicate that primary deficits compensate the changes in liabilities to help limit debt accumulation. Walsh (2003) classified this as a traditional analysis in which fiscal policy always adjust to ensure government’s intertemporal budget identity while monetary policy is free to set nominal money stock or nominal of interest rate. 12 Komulaenen and Pirttilä (200) used other VAR technique to investigate empirically fiscal and monetary dominance issue 126 A second type of shock is to consider the effect of current primary balance innovation to future additional debt. The FD will appear if there is no significant impact on the additional future debt of the positive innovation of primary balance. Meanwhile, the MD will occur in this type of shock if current innovation to the primary deficit should be positively related to the additional future government debt and hence adlt. This figure imply that if the government run the surplus primary balance then it can pay down the debt and hence reduce additional future debt. Another interpretation also appears in MD regime if we extend the assumption to a variable real interest rate. Under this scenario, negative relationship between primary balance innovation and future debt should appear because it reflect a negative government response of reduction of primary deficit by lower (higher) expected future interest payment and hence could make a more (less) additional borrowing. Table 2 reproduce Tanner and Ramos (2002) economic interpretation of the VAR system result regarding to the issues. 3.2. Empirical Result: Fiscal plays a dominant role Employing quarterly data since 1984:2 to 2003:2, the estimations are grouped into three sub-periods as indicated by QFA result i.e. period prior 1990, period between 1990 and 1997 and period after 1997. Some quarterly raw data are obtained from author’s calculations from old government 127 budget format. Since the quarterly data for external government debt stock is not available prior 1990, the external debt stock before 1990 was calculated from net inflow government debt from balance of payment data of Bank Indonesia. The primary surplus/deficit of government prior 1997 is generated by excluding the interest and principal repayment foreign government debt from government budget. The estimation result apparently confirms the QFA result estimation. The Granger causality test in table 3 indicates the whole sample does not provide a significant relationship between primary balance and additional debt required to finance the operational deficit. This performance generally was supported from the sub-periods prior 1990 that do not demonstrate a considerable relationship. The significant and negative relationship between those two variables only appears in period between 1990 and 1997. This 1990-1997 result is not a surprise result. Empirical data support this indication. An accumulated primary surplus was move contrastingly to the decreasing of the ratio of foreign government debt to GDP which somehow could imply some sustainable fiscal policy. The Granger causality test is also supported by impulse response function of VAR result that implied an effort from fiscal policy to response future debt growth by accumulating the government primary surplus. For period prior 1990 and since 1997 the impulse response function does not show a significant response to the each innovation, regardless the order. The significant impact only appear in period between 1990 and 1997 where 128 the impulse response function for 1990-1997 period estimation obtain a negative and significant changes on public liabilities to an innovation of primary surplus for at least 1-2 periods (Table 4). For period after 1997, Granger causality test provides an insignificant figure. In addition to the result, impulse response function of VAR system also obtained similar idea. The response of public liabilities to primary surplus innovation provides an insignificant impact, regardless the ordering. This result indeed slightly confirms the QFA estimation that posed a deficit number since the crises occurred. These results imply further description of fiscal and monetary policy interaction. The period 1990-1997 indicates that the central government have slightly succeeded to pursue a debt management. Government has sufficiently reduced the future debt as responses of primary budget surplus. The impulse response function in this period indicated that a positive shock of current primary surplus has negatively affected the future liabilities. Supporting the argument, QFAwas also quite neutral such that not sufficient enough to classify monetary policy as sub-ordinate of fiscal policy. At some degree, the result of period 1990-1997 indicates that monetary policy played dominant role with respect to fiscal and monetary policy interaction. Nevertheless the story changed abruptly while the crises hit the mid of 1997. Although the lack of observation numbers may affect the story, the result indicated a different portrait appeared. The sharp and huge depreciation of domestic currency, big amount of issuing additional domestic 129 debt and the unavoidable liquidity support from central bank policy in 1997 – 1999 consecutively brought a big burden to fiscal policy such that also involved monetary policy. This performance apparently indicates that fiscal policy play more exogenously in this regime. Indeed, the study has also tried to exclude the central bank securities to capture ‘real’ government debt and to see its response to the primary balance performance. However, the result does not change and keep showing similar conclusion. 4. Implication for Inflation Targeting in Indonesia The results from two previous parts suggest several summaries to fiscal and monetary policy interaction in Indonesia. First, prior crises 1997, generally fiscal policy have ensured fiscal sustainability by accumulating primary surplus to reduce the debt ratio to GDP. Following Leeper (1991) terms, fiscal policy during this period tended to be a passive policy because it always tried to satisfy government budget constraint13. Meanwhile, monetary policy plays an active role which was confirmed by neutral position of QFA. This result apparently shows that fiscal policy commitment on fiscal solvency lead macroeconomic policy during 19901997 under monetary dominance regime. Second, since the 1997 the fiscal and monetary policy interaction exhibits a big different portrait. Fiscal policy seems not be able to generate sufficient amount of primary surplus balance to cover the rise of government debt both from external and domestic debt. Banking crises also generated deficit in QFA since 1998 which was mostly caused by central bank liquidity support to banking system. In addition, government policies to withdraw their deposit in central bank also provide another reason the emergence of QFA. In general, those environments tend to lead the conclusion fiscal policy behaves exogenously in view of fiscal and monetary interaction framework since 1997. 13 Leeper (1991) defined passive fiscal policy as a situation in which fiscal policy always adjust their primary balance to satisfy government’s intertemporal budget. On contrast, if fiscal policy is set independently such that could generate seigniorage from monetary authority then fiscal policy is defined under active fiscal policy. 130 How this fiscal and monetary interaction result could affect central bank objective to control inflation, amid the environment monetary policy independence probably has increased due to the new central bank law enacted in 1999? Referring to Leeper (1991) terms, the result of fiscal and monetary interaction after 1997 and also higher independent in monetary policy could implies both active in fiscal and monetary policy regime was occurred in Indonesia since 1999. Fiscal policy is exogenous to debt performance while monetary policy restraint the policy only to inflation. This macroeconomic policy environment has different implications to the effectiveness monetary policy objective to control the inflation even under inflation targeting framework which has been adopted by Indonesia. Much of discussion corresponds to the implication of those fiscal and monetary policy stance on inflation behaviour were put under fiscal theory of price level (FTPL) literature14. Under this theory, inflation is not the sole of territory of the central bank but it is also contributed by fiscal authority. Carlstrom and Fuerst (1999, 2000) summarized two version of FTPL namely weak form FTPL and strong form FTPL. Under weak form FTPL which is parallel to fiscal dominance environment in this paper, inflation is indeed monetary phenomenon but money growth is dictated by fiscal authority because an increase in future deficits must result in either one time increase in money (a one-time jump in the price level) or an increase in future money growth (future inflation). This form is analogy to game of chicken emerges in which monetary authority loses and is forced to “blink” for this behaviour. Meanwhile the strong form FTPL argues that even if money growth is unchanged, fiscal policy independently affect price level and inflation rate. Strong FTPL assumes that in order to uniquely determine price, the additional restriction of government budget constraint is needed. Prices will adjust so that the real of government debt can adjust to a level consistent with the fiscal budget constraint even if monetary policy is unchanged. To summarize, those two form of FTPL subsequently imply that the central 14 See Leeper (1991), Koncherlakota and Phelan (1999), Cochrane (1998) and Woodford (1996, 2001) and Walsh (2003) for FTPL literature. 131 bank is plausibly in-effective to commit to an inflation target, either because central bank does not control the money supply (weak form) or because inflation is not necessarily a monetary phenomenon (strong form). Does this FTPL emerge in Indonesia in the period after 1997? This is empirical question and even still provides long line debatable answers for the plausible existence of the theory for strong form FTPL15. Carlstrom and Fuerst (1999, 2000) argued that strong FTPL has some empirical problem because it needs large elasticity in real interest rate in order for self-fulfilling circle to occur. The large real interest rate that is apparently unrealistic since it requires three large elasticity: (1) a large interest of money demand; (2) a large response of output to a decline in real balances and (3) large response of the real to decline in current output. Parallel to Carlstrom and Fuerst (1999, 2000) argument, strong form of FTPL is unlikely present in the case of Indonesia because all those assumptions seem not appear in Indonesia economy as suggested in recent empirical studies in Indonesia regarding to those issue 16. From the weak form of FTPL, the empirical situations in Indonesia also show similar hints to strong form. So far, weak form of FTPL cannot be identified clearly especially since 1999 when the central bank obtained more monetary policy independence through the new central bank act. Since that time, central bank does not provide Bank Indonesia liquidity credit (KLBI) as shown before 1999. In addition, the new act also prohibits government intervention to monetary policy including seigniorage from the central bank. Despite QFA by central bank show deficit number, some evidences support the idea that fiscal policy keep trying to avoid financing from central bank. Except in 2003, domestic financing from central bank tend to be negative which implies accumulating government deposit in the central bank. Instead, the sources of deficit financing were source from government bond issuance and privatization of state enterprises. In addition to it, base money also grew at a low level. 15 Some critics relates to the existence of FTPL see Carlstrom and Fuerst (1999, 2000), Buiter (2002, 2001, 1999), 16 Among others see Anglingkusumo (2004) and Simorangkir (2002) that examined demand for money function in Indonesia. Macroeconometric model of Bank Indonesia (MODBI) also show a small elasticity result of interest rate impact on output. 132 To sum up, the empirical data identified cannot clearly identify FTPL occurrence in Indonesia since 1999 for both strong and weak from of FTPL. The QFA in central bank seems can be classified into monetary policy discretion due to liquidity support problem. Meanwhile the fiscal dominance conclusion using VAR approach in part three test might still be an ambiguous result due to the lack of data. Zoli (2004) employed data from some emerging countries argues that VAR method could provide an ambiguous result. This result implies that monetary policy could be still dominance in term of fiscal and monetary interaction since period 1999. Despite those empirical results rejection on FTPL and the tendency of monetary policy dominance in Indonesia, some literatures still show that fiscal performance can still affect the effectiveness of monetary policy even under inflation targeting. Using Brazil experience, Blanchard (2004) indicated that expectation channel of fiscal performance deterioration could cause a reversal effect of monetary policy to control inflation. Employing fiscal dominance term to represent the deterioration of domestic government debt, Blanchard (2004) pointed out that the tight monetary policy by raising real interest rate could increase the probability of default on debt which may affect domestic government debt less attractive and eventually to lead a real depreciation. If the government debt also contains foreign currency denominated debt, the real depreciation of domestic currency could even lead higher price of risk. Under this circumstance, Blanchard (2004) proposed that inflation targeting can clearly have perverse affects: an increase in the real interest rate in response to higher inflation will lead to real depreciation which sequentially in turn to a further increase in inflation. The result implied that fiscal is dominance and the solution should be from the fiscal policy. Consistent with this result, Favero and Giavazzi (2004) also argued that default risk is at the centre of mechanism through which a central bank that targets inflation might lose control of inflation. In addition, Loyo (1999) argued that fiscal performance may interrupt the effectiveness of monetary policy through the wealth effect if government has domestic debt problem. Under this circumstance, using Brazil for the 133 case, Loyo (1999) argued that higher interest rate by central bank could induce higher outside financial wealth of private agents in nominal terms which could generate higher consumption and finally higher inflation. If monetary policy responds to higher inflation with sufficiently higher nominal interest rate, a vicious circle will emerge. Again, fiscal dominance interrupts monetary policy effectiveness even under inflation targeting framework. Graph 6 Indonesia’s Sovereign Bond Spread, Rupiah Exchange Rate and Public Debt Ratio to GDP Source: Bloomberg, Ministry of Finance and Bank Indonesia 134 How might all these other channel of fiscal dominance apply to Indonesia? Although required further empirical confirmation, at least those other channel could motivate to a more prudence and discipline in fiscal sustainability aspect. Indeed, some indicator in Indonesia obtains similar type of Brazilian case where government debt performance provides parallel path to Indonesia’s sovereign bond spread (Graph 6). If this spread tied to probability of default as Blanchard’s argument then the higher government debt ratio will cause higher probability default of the debt. Under this circumstance, central bank would confront higher challenge associated with the effectiveness of inflation targeting, as argued before. This environment also appears in other emerging countries as pointed by BIS for positive correlation between public debt to GDP ratio performance and sovereign bond spread. Following Cochrane (2003) argument, this idea implied that implementation inflation targeting in Indonesia also need fiscal consideration and commitment ability to conduct a monetary framework. BIS (2003) discussed the importance of fiscal discipline to the effectiveness of monetary policy to control the inflation17. In operational point of view, implementation of interest rate rule in conducting monetary policy requires a greater fiscal discipline and commitment ability to control government debt performance. Furthermore Sims (2003) argued that inflation targeting framework needs an appropriate coordination with or back up by fiscal policy. The nature of the required coordination will depend on whether and how central bank independence from the fiscal authority has been implemented. In sense of debt performance, Buiter (2004) suggest that for country with weak economic and political situation, the safe level of the net public debt to GDP ratio is likely to be low. Further than that, Reinhart, Rogoff and Savastano (2003) argued that developing countries with a poor track record have a very limited capacity for carrying public debt, internal and external. For external debt, they calculated that the ‘safe’ threshold for highly debt intolerant emerging market may be as low as 20 percent of GDP. 17 See Mihaljek and Tissot (2003) and Moreno (2003) for detail discussion 135 5. Concluding Remark The main purpose of the paper is not to test Indonesia’s fiscal solvency and neither to solve the fiscal insolvency if it was occurred. Nevertheless, the paper inevitably still touches the idea of fiscal solvency and indirectly also implies to effect of monetary objective to control inflation. Fiscal and monetary interaction analysis in this paper found that the crisis has generated QFA by central bank. Further result also shows that fiscal policy play in a dominancerole in fiscal and monetary interaction in Indonesia post 1997, though it can be classified in weak form. Does this result matter for monetary policy objective to control inflation in Indonesiawhile since 1999 the new central bank law has provided an independence of monetary policy? This paper carefully implies the answer is yes. Fiscal and monetary policy interaction performances lead to the implication that monetary policy under inflation targeting framework in Indonesia still call fora higherfiscal discipline and commitment of the government to maintain the sustainability. The failure to solve fiscal performance optimally could deteriorate monetary policy effectiveness to control inflation even under inflation targeting framework. The emergence of fiscal dominance particularly from public expectation and wealth effect channel on debt performance could bring tight monetary policy paradox. Under this circumstance, inflation targeting can have perverse affects: an increase in the real interest rate to respond higher inflation will lead to real depreciation which sequentially in turn to a further increase in inflation. The result implied the solution to control inflation should be from the fiscal policy not solely from monetary policy. 136 Reference Anglingkusumo, Reza (2004), “Stability of The Demand for Real Narrow Money in Indonesia: Evidence from The Pre and Post Asian Crisis Era”, Vrije Universiteit and Tinbergen Institute – Amsterdam, manuscript Bank for International Settlements (2004), “The Changing Interest rate Environment and Debt Sustainability in the Emerging Market Economies”, Note for non-G10 Governors meeting, 27 June Bank Indonesia, Annual Report 1997/1998 and 1998/1999 issues Blanchard, Olivier (2004), “Fiscal Dominance and Inflation Targeting: Lesson from Brazil”, NBER WP 10389, March Boediono (2004), “Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya” (Current and Future Fiscal Policy), in Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi (Fiscal Policy: Thought, Concept and Implementation), H. Subiantoro and S. Riphat, eds, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Beckerman, Paul (1995), “Central Bank ‘Distress’ and Hyperinflation in Argentina 1989-90”, Journal of Latin American Studies, 27, pp. 663-681 Budina, N., and Wijnbergen S., (2000), “Fiscal Deficit, Monetary Reform and Inflation Stabilization in Romania”, World Bank Working Paper Series no. 2298 Buiter, Willem H. (2004), “Fiscal Sustainability”, available at http://www. nber.org/~wbuiter/ public.htm, 6 January Buiter, Willem H. (2002), “The Fiscal Theory of the Price Level: A Critique”, Economic Journal, Vol 112, July 2002, pp. 459-480 Buiter, Willem H. (2001) “The Fallacy of the Fiscal Theory of the Price Level, Again”, Bank of England Working Paper Series No. 141, July 137 Buiter, Willem H. (1999), “The Fallacy of the Fiscal Theory of the Price Level”, NBER Working Paper No. W7302, August Buiter, Willem H. (1993), “Consistency Check for Fiscal, Financial and Monetary Policy Evaluation and Design”, mimeo, World Bank, October Carlstrom, Charles T. and Timothy S. Fuerst (2000), “The Fiscal Theory of the Price Level,” Economic Review, (Q I) pp. 22-32. Federal Reserve Bank of Cleveland Carlstrom, Charles T. and Fuerst (1999), “Money Growth and Inflation: Does Fiscal Policy Matter?”, Economic Commentary, Federal Reserve Bank of Cleveland, April 15 Campbell, John Y. (1987), “Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of The Permanent Income Hypothesis”, Econometrica, Vol. 55, November, pp. 1249-73 Canzoneri, Matthew B., Robert E. Cumby and Behzad T. Diba (2001), “Is the Price Level Determined by the Needs of Fiscal Solvency?”, American Economic Review, 91(5), December, 1221-1238 Cochrane, John M (2003), “Fiscal Foundation of Monetary Regime” paper presented at 2003 NBER/NCAER Neemrana Conference, available at http://gsbwww.uchicago.edu/fac/john.cochrane/research/Papers/ indiafiscal.pdf Cochrane, John M (1998), “A Cashless View of U.S. Inflation,” in Be S. Bernanke and Julio Rotemberg, eds., NBER Macroeconomic Annual Cambridge, Mass.: MIT Press, pp.323-84 Favero, Carlo A. and Fransesco Giavazzi (2004), “Inflation Targeting and Debt: Lesson from Brazil”, NBER WP 10389, March Hawkin, John (2004), “Central Bank Securities and Government Debt”, paper presented to Australasian Macroeconomic Workshop Australian National University, Canberra, 15-16 April Hawkin, John (1999), “Bank Restructuring in South-East Asia”, BIS Policy Paper, September 138 Komulainen, Tuomas and Jukka Pirttilä (2000), “Fiscal Explanation for Inflation: Any Evidence from Transition Economies”, Bank of Finland Discussion Papers, No.11 Koncherlakota, Narayana and Christhoper Phelan (1999), “Explaining the Fiscal Theory of the Price Level,” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 23, 14-23 Leeper, Eric M. (1991), “Equilibria under ‘Active’ and ‘Passive’ Monetary and Fiscal Policies”, Journal of Monetary Economics, 27, February, 129-147 Loyo, E (1999), “Tight Money Paradox on the Loose: A Fiscalist Hyperinflation”, mimeo, Kennedy School of Government, June Mackenzie, G.A. and Peter Stella (1996), “Quasi-Fiscal Operations of Public Financial Institution”, IMF Occasional Paper, 142, October Markiewicz, Malgorzata, (2001), “Quasi-fiscal Operations of Central Banks in Transition Economies”, Bank of Finland Discussion Papers, No.2 Mihaljek, Dubravko and Bruno Tissot (2003), “Fiscal Positions in Emerging Economies: Central Bank’s Perspective”, BIS Papers No.20, October Moreno, Ramon (2003), “Fiscal Issues and Central Banking in Emerging Economies: an Overview”, BIS Papers No.20, October Reinhart, Carmen M., Kenneth S. Rogoff and Miguel A. Savastano (2003), “Debt Intolerance”, NBER Working Paper No. 9908, August Rodriguez, Carlos A. (1994), “Argentina: Fiscal Disequilibria Leading to Hyperinflation”, in “Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance”, William E., Carlos A.R., an Klaus Schmidt-Hebbel, eds, The World Bank Sargent, Thomas and Neil Wallace (1981), “Some Unpleasent Monetarist Arithmetic”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 5, Fall 1-17 139 Simorangkir, Iskandar (2002), “Financial Deregulation and Demand for Money in Indonesia”, Buletin Ekonomi dan Perbankan Vol. 5 No.1, June, 1-17 Sims, Christhoper A. (2003), “Limit to Inflation Targeting”, mimeo, PrincetonUniversity Stella, Peter (1997), “Do Central Banks Need Capital”, IMF Working Paper 83, July Tanner, Evan and Alberto M. Ramos (2002), “Fiscal Sustainability and Monetary versus Fiscal Dominance: Evidence from Brazil, 19912000, IMF Working Paper, No. 5, January Van’t dack, Jozef (1999), “Implementing Monetary Policy in Emerging Market Economies: An Overview of Issues”, BIS Policy Papers, No. 5, March Walsh, Carl (2003), Monetary Theory and Policy, 2nd Edition, (Cambridge, MA: The MIT Press) Woodford, Michael (1996), “Control of the Public Debt: A Requirement for Price Stability?”, NBER WP 5684 Woodford, Michael (2001),”Fiscal Requirements for Price Stability”, Journal of Money, Credit and Banking 33: 669-728 Zoli, Edda (2004), “How Does Fiscal Policy Affect Monetary Policy In Emerging Market Countries?”, BIS, draft 140 PERANAN ASA NALAR DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN R. Maryatmo1 Pendahuluan D ua pertanyaan besar dicoba dijawab dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan apakah kebijakan defisit anggaran mempengaruhi perekonomian pada umumnya dan variabel moneter khususnya. Jika kebijakan defisit anggaran mempengaruhi variabel moneter, maka bank sentral yang independen perlu melakukan koordinasi secara erat dengan penguasa fiskal. Kedua, penelitian ini mencoba mencari jawab apakah masyarakat Indonesia rasional. Jika rasional, maka masyarakat Indonesia akan mampu belajar dari pengalaman dan menggunakan seluruh informasi yang dimiliki secara efisien guna mendukung keputusan ekonominya. Kedua pertanyaan tersebut akan dicoba dicari jawabnya satu persatu. Ada dua hal baru yang mampu disajikan oleh hasil penelitian ini. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian dampak moneter kebijakan defisit anggaran di Indonesia dengan menggunakan model persamaan simultan dengan cakupan data terbaru. Kedua, penelitian ini menyertakan variabel asa nalar (rational expectation) yang merupakan bidang kajian yang relatif baru di Indonesia. Penelitian-penelitan sebelumnya memakai model dinamik yang ke belakang (backward), seperti PAM, Koyck, AR, MA, atau ARIMA. Model dinamis yang ke belakang menghasilkan prediksi yang pasti bias ke bawah jika tren meningkat dan bias ke atas jika tren menurun. Model asa nalar atau harapan rasional (rational expectation) dengan variabel 1 Dosen IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogjakarta. 141 ke depan mampu memprediksi lebih akurat dan pelaku ekonomi dapat belajar dari kesalahan masa lampau dan menggunakan informasi terkini secara efisien guna mendukung keputusan ekonominya. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, kebijakan defisit anggaran selalu menjadi andalan pemerintah Indonesia. Kebijakan defisit anggaran tersebut didanai oleh utang luar negeri (periode Orde Lama dan Orde Baru), dan oleh pencetakan uang (Orde Lama), serta oleh penjualan Surat Utang Negara (Orde Reformasi). Kebijakan defisit anggaran seperti tidak pernah dipertanyakan efektivitas dan efisiensinya. Yang dipertanyakan biasanya adalah sumber pendanaan defisit yang berasal dari hutang luar negeri. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kebijakan defisit anggaran yang selalu dijalankan pemerintah tersebut bermanfaat terhadap perekonomian Indonesia. Secara lebih spesifik, apakah defisit anggaran mempengaruhi variabel moneter seperti suku bunga, kurs, dan tingkat harga. Jawaban teoritik dan empirik dampak moneter kebijakan defisit anggaran dicoba digali dalam penelitian ini. Penelusuran teoritik dampak moneter kebijakan defisit anggaran pemerintah sangatlah menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan tersebut menarik karena di dalamnya penuh silang pendapat yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Paling tidak ada tiga kelompok yang menyodorkan jawaban teoritik yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok Ricardian yang terkenal dengan teorinya Ricardian Equivalence (RE). Kelompok Ricardian mengatakan bahwa kebijakan defisit anggaran tidak mempengaruhi perekonomian, sehingga mereka tidak merekomendasikan dijalankannya kebijakan fiskal defisit anggaran. Kesimpulan mereka ditopang oleh asumsi-asumsi yang mendasarinya. Mereka mengasumsikan bahwa sebuah negara terdiri dari sekelompok bangsa yang padu dan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup anak cucu mereka di masa depan. Diasumsikan pula mereka mengetahui secara sempurna segala kebijakan yang dilakukan dan direncanaan pemerintah, termasuk kebijakan defisit anggaran. Mereka mengetahui bahwa jika pemerintah melakukan kebijakan defisit anggaran 142 di masa sekarang, maka pemerintah pasti akan memberi beban pajak yang tinggi di masa yang akan datang kepada anak cucu mereka. Jika mereka mengetahui bahwa pemerintah akan membebani pajak kepada anak cucu mereka di masa yang akan datang, maka mereka akan menabung di masa sekarang. Kebijakan defisit anggaran tidak meningkatkan permintaan karena peningkatan pendapatan disalurkan ke tabungan untuk berjagajaga terhadap peningkatan beban pajak di masa yang akan datang. Dengan demikian defisit anggaran tidak efektif. Kelompok kedua adalah kelompok Neoklasik. Kelompok Neoklasik menyimpulkan bahwa kebijakan defisit anggaran cenderung merugikan perekonomian. Menurut mereka hubungan kekerabatan antargenerasi renggang. Mereka mengetahui bahwa kebijakan defisit anggaran di masa sekarang berarti memberikan beban pajak kepada anak cucu mereka, tetapi mereka tetap melaksanakannya. Karena mereka tidak peduli terhadap peningkatan beban pajak anak cucu mereka di masa yang akan datang, mereka menjawab kebijakan defisit anggaran mereka dengan peningkatan konsumsi di masa sekarang. Jika kondisi perekonomian sudah dalam kesempatan kerja penuh (full employment), maka peningkatan konsumsi mengakibatkan pengurangan tabungan dan meningkatnya suku bunga. Peningkatan suku bunga selanjutnya menyebabkan turunnya investasi (crowding out) dan pendapatan nasional. Kelompok ketiga adalah kelompok Keynesian. Kelompok Keynesian berpendapat bahwa kebijakan defisit anggaran akan mendorong perekonomian, sehingga mereka mendukung kebijakan defisit anggaran. Mereka memfokuskan perhatian dalam jangka pendek dan mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi tidak berfikir dalam jangka panjang (myopic). Jika pelaku ekonomi hanya berfikir jangka pendek, maka defisit anggaran yang meningkatkan pendapatan masyarakat dijawab dengan peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi dan juga permintaan agregat mendorong peningkatan produksi. Pertanyaan kedua yang ingin dicari jawabnya dalam penelitian ini ialah apakah masyarakat Indonesia rasional. Jika rasional, maka masyarakat 143 Indonesia akan mampu belajar dari pengalaman dan menggunakan seluruh informasi yang dimiliki secara efisien guna mendukung keputusan ekonomi yang dibuatnya. Jika masyarakat Indonesia rasional, maka mereka mampu mengubah perilaku guna mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat yang rasional secara bersama-sama tidak akan pernah salah secara sistematis dalam meramalkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk menjawab kedua pertanyaan besar itu, dibangun model persamaan simultan. Model dibangun dengan menggunakan pendekatan perilaku (teori optimasi), model koreksi kesalahan (ECM), dan menyertakan variabel kejutan (shock), serta asa nalar (rational expectation). Perekonomian Indonesia mengalami beberapa kali perubahan struktural, yang berarti pelaku ekonomi melakukan perubahan perilaku. Secara teoritik penyertaan variabel kejutan, asa nalar, dan pembentukan Model Koreksi Kesalahan memungkinkan agen ekonomi mampu tidak hanya belajar dari pengalaman masa lampau namun juga menggunakan informasi terkini untuk mengantisipasi kejutan terbaru. Pelaku ekonomi mampu belajar dari pengalaman. Jika mampu menggunakan informasi terkini, maka pelaku ekonomi dalam model mampu mengubah perilaku sesuai dengan tuntutan kondisi pada saat itu. Pengertian dan Sifat Nalar Pelaku Ekonomi Ada beberapa pertanyaan mendasar yang menggantung, yakni mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku ekonomi yang nalar? Seperti apakah sifat-sifat pelaku ekonomi yang nalar? Apakah betul pelaku ekonomi dapat bersifat nalar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas sebagai berikut. Secara implisit dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku ekonomi yang nalar ialah seorang pelaku ekonomi yang mampu menggunakan seluruh informasi yang dimiliki, baik informasi masa lampau, maupun informasi terkini pada saat pelaku ekonomi akan membuat keputusan ekonominya secara efisien (Grossman, 1980). Dengan kemampuan menggunakan 144 informasi yang dimiliki tersebut, pelaku ekonomi yang nalar tidak akan membuat kesalahan secara sistematis dalam membuat keputusannya. Pelaku ekonomi yang nalar tidak berarti tidak pernah membuat kesalahan, namun secara bersama, dan rata-rata mereka mampu melakukan keputusan secara tepat. Secara ekonometrik sifat-sifat di atas dapat diformulasikan sebagai berikut (Holden, et.al., 1985). Pertama, pelaku ekonomi yang nalar mempunyai rata-rata kesalahan sama dengan nol, dan pelaku ekonomi mampu belajar dari kesalahan sehingga kesalahan yang terdahulu tidak mempengaruhi terjadinya kesalahan pada periode berikutnya. Walaupun pelaku ekonomi nalar, namun bukan berarti pelaku ekonomi tidak membuat kesalahan. Pelaku ekonomi tetap mungkin membuat kesalahan, namun kesalahan itu tidak bersifat sistematis, dan secara rata-rata pelaku ekonomi membuat keputusan yang benar. Kesalahan keputusan pelaku ekonomi bersifat acak. Kedua, pelaku ekonomi yang nalar mampu menggunakan informasi secara efisien, sehingga kesalahan pelaku ekonomi minimal. Kesalahan pelaku ekonomi minimal, karena pelaku ekonomi mampu belajar dari kesalahan masa lalu, dan mampu mengakses informasi terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan yang serupa. Tidak ada korelasi antara kesalahan masa lalu dan kesalahan di masa sekarang. Ketiga, pelaku ekonomi yang nalar akan membuat kesalahan peramalan yang saling berkorelasi. Kesalahan peramalan tersebut tidak berkorelasi dengan informasi terkini yang dimiliki pelaku ekonomi, pada saat pelaku ekonomi membuat keputusan peramalan. Jika ada korelasi antara informasi terkini yang dimiliki pelaku ekonomi dan kesalahan peramalan, maka pelaku ekonomi mampu meningkatkan kemampuan peramalan. Apakah benar pelaku ekonomi selalu nalar? Apakah benar kesalahan pelaku ekonomi tidak akan bersifat sistematis? Dalam kenyataannya, dalam jangka pendek banyak pelaku ekonomi yang tidak mampu mendapatkan akses informasi terkini, sehingga keputusan ekonominya hanya berlandaskan pada pengalaman masa lampau. Jika pelaku ekonomi hanya mengandalkan 145 informasi pada masa lampau, maka kesalahan pelaku ekonomi akan bersifat sistematis. Kesalahan masa lampau akan mempengaruhi terjadinya kesalahan di periode berikutnya. Dalam jangka panjang mestinya pelaku ekonomi mampu belajar dari kesalahan masa lalu, sehingga mengupayakan informasi terbaik guna menunjang keputusan ekonominya. Jika pelaku ekonomi mampu meningkatkan penggunaan informasinya, dan tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lampau saja, maka pelaku ekonomi semakin nalar. Secara statistik apakah pelaku ekonomi dalam jangka panjang sungguh nalar dapat akan dibuktikan dalam uji asa nalar. Penurunan Model Asa Nalar Sebuah pertanyaan penting adalah bagaimana variabel asa nalar dapat masuk dalam model perekonomian. Tentu variabel asa nalar tidak tiba tiba masuk ke dalam model. Sub-bab berikut ini akan membahas contoh bagaimana variabel asa nalar masuk dalam model, secara khusus adalah teori perilaku konsumsi yang melibatkan asa nalar masyarakat dalam membuat keputusan. Barang yang dikonsumsi oleh pelaku ekonomi adalah barang produksi dalam negeri dan barang produksi luar negeri (impor). Pelaku ekonomi domestik yang mengkonsumsi adalah rumah tangga (household), pelaku bisnis (enterpreuner), dan pemerintah (government). Pelaku ekonomi yang hidup dalam dua periode bertindak nalar dan selalu mengupayakan untuk mengoptimalkan utilitasnya dengan kendala anggaran antarwaktu. Kendala antarwaktu menunjukkan nilai anggaran sepanjang masa (dua periode) yang diukur dengan nilai sekarang (present value) guna dialokasikan untuk konsumsi dua barang yakni barang impor dan barang produksi dalam negeri selama dua periode. Dalam model antarwaktu ini, pelaku ekonomi dapat mengkonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit tingkat pendapatan pada periode yang sama. Jika pada waktu t pelaku ekonomi mengkonsumsi lebih banyak dari aliran pendapatan (disposable income) pada waktu t, maka pelaku ekonomi harus meminjam dana. Jika pada waktu t pelaku ekonomi mengkonsumsi lebih sedikit dari aliran pendapatan pada periode waktu t yang sama, maka pelaku ekonomi menabung guna dibelanjakan di periode 146 waktu berikutnya. st = at – ( pd e pm ct + mt) pa pa (1) di mana st = tabungan riil pada waktu t at = pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) riil pada waktu t, yang dihasilkan dari tingkat pendapatan dikurangi pajak (yt - txt) ct = konsumsi riil dari produk dalam negeri pada waktu t mt = konsumsi riil produk impor pada waktu t Seperti dijelaskan, st bisa bernilai positif atau negatif. Dengan demikian konsumsi yang akan datang (Ect+1 + Emt+1) dapat didanai oleh pendapatan yang siap dibelanjakan di masa yang akan datang ditambah nilai tabungan st dan nilai bunganya (E at+1+(1+i)st). (2) Di depan variabel konsumsi dan pendapatan yang siap dibelanjakan di masa yang akan datang disertai notasi E, yang mewakili asa pelaku ekonomi, karena masa yang akan datang terdapat unsur ketidak pastian. Persamaan (1) dan (2) dapat digabung menjadi persamaan (3). (3) Persamaan (3) dapat dituliskan menjadi persamaan anggaran dua periode waktu yang dapat dituliskan sebagai berikut. (4) Persamaan (4) mengatakan bahwa konsumsi sepanjang masa hanya akan didanai oleh pendapatan yang siap dibelanjakan selama periode yang sama. Orang lahir tidak membawa apa-apa, dan meninggal tanpa meninggalkan warisan pula. 147 Dalam mengalokasikan anggaran tersebut, pelaku ekonomi mengacu pada preferensinya yang diwakili oleh fungsi utilitas yang dapat dituliskan: (5) Notasi E menunjukkan preferensi waktu pelaku ekonomi. Peningkatan konsumsi produk dalam negeri, ct, maupun produk impor, mt, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang akan meningkatkan utilitas konsumen, yakni Diasumsikan pula bahwa marginal utilitas pelaku ekonomi itu mengalami penurunan (decreasing marginal utility), sehingga turunan kedua dari fungsi utilitas akan negatif. Kondisi tersebut memungkinkan adanya tingkat kepuasan maksimal pelaku ekonomi. Diasumsikan pelaku ekonomi selalu mengupayakan untuk mencapai utilitas maksimal dengan kendala anggaran. Proses maksimisasi utilitas dapat dilakukan dengan metode Lagrange yang persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut. 148 Persamaan (8), (9), (10), dan (11) akan menghasilkan persamaan diferen permintaan konsumsi produk dalam negeri (ct), dan permintaan barang impor (mt). (16) Persamaan (13) dan (14) mengatakan bahwa pelaku ekonomi mempunyai preferensi yang sama antara nilai diskonto permintaan konsumsi produk dalam negeri dan produk impor yang diharapkan di masa yang akan datang dengan nilai konsumsi produk dalam negeri dan produk impor di masa sekarang. Selanjutnya solusi time path dari ct dan mt akan diperoleh dengan mensubstitusikan nilai E ct+1, dan E mt+1 dari persamaan (12) ke dalam persamaan (13) dan (14), sehingga diperoleh persamaan dinamis permintaan konsumsi ct dan mt, yang secara umum merupakan (17) Jika tingkat pendapatan pada waktu t ataupun tingkat pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang meningkat, maka tingkat konsumsi pada masa sekarang meningkat juga meningkat. Sedangkan 149 Kesimpulan teoritik di atas mengatakan bahwa jika tingkat harga domestik (pa) di masa kini maupun di masa yang akan datang meningkat, maka konsumsi domestik (ct) turun. Demikian pula jika harga produksi dalam negeri meningkat (pd), baik sekarang maupun di masa yang akan datang, maka konsumsi domestik (ct) turun. Jika suku bunga (i) meningkat, berarti menabung untuk konsumsi di masa yang akan datang lebih menarik, maka konsumsi di masa sekarang turun. Jika E meningkat, yang berarti preferensi terhadap konsumsi di masa yang akan datang meningkat, maka konsumsi pada masa sekarang turun. Yang terakhir, jika tingkat substitusi marginal (marginal rate of substitution) (I) dari konsumsi barang impor terhadap barang produksi dalam negeri meningkat, yang berarti untuk mendapatkan satu unit konsumsi dalam negeri membutuhkan pengorbanan barang impor lebih banyak dalam rangka mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, maka konsumsi dalam negeri akan menurun. Reduced form untuk persamaan permintaan impor adalah: (18) Dari persamaan di atas (18) dapat disimpulkan bahwa permintaan impor akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan baik pada waktu t maupun pada waktu t+1. Secara matematis dapat dituliskan : ∂mt/ ∂at > 0, ∂mt/ ∂at+1 > 0 Demikian pula jika tingkat harga barang impor dalam dolar meningkat pada waktu sekarang, maka konsumen akan cenderung mengurangi konsumsi barang impor. Jika kurs pada waktu sekarang meningkat, berarti rupiah melemah dan berarti harga barang impor dalam rupiah meningkat, maka konsumsi barang impor akan turun. Jika suku bunga meningkat, maka lebih menarik untuk menabung, sehingga anggaran yang dibelanjakan pada waktu sekarang berkurang, sehingga konsumsi barang impor juga turun. Jika preferensi waktu terhadap uang meningkat, berarti masyarakat lebih menyukai lebih sejahtera di masa yang akan datang dengan cara 150 mengurangi konsumsi di masa sekarang, maka ada kecenderungan impor pada waktu sekarang turun. Akhirnya, jika masyarakat mengharapkan kurs dan harga impor di masa yang akan datang meningkat, berarti daya beli uang di masa yang akan datang turun, sehingga untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama masyarakat harus menabung dan mengurangi konsumsi pada waktu sekarang, termasuk konsumsi barang impor. Uraian di atas secara ringkas dapat dinyatakan seperti terlihat dalam pernyataan matematis berikut ini. ∂mt/ ∂pmt < 0, ∂mt/ ∂et < 0, ∂mt/ ∂i < 0, ∂mt/ ∂E < 0, ∂mt/ ∂I < 0, ∂mt/ ∂pmt+1 < 0, ∂mt/ ∂et+1 < 0 Secara arbitrer, persamaan (16) dan (17) dapat dispesifikasikan dalam persamaan ekonometris sebagai berikut. ct =D 10 + D11 it + D12 at +D13 Eat+1 + e10 (19) mt = D20 + D21 (epm/pa) + D22 at + e20 (20) di mana D11 <0, D12 > 0, D13 > 0, D21 <0 , D22 > 0 Pembentukan Asa Nalar Sub bab ini akan membahas terbentuknya asa nalar dalam model perekonomian. Tujuan dari formulasi terbentuknya asa nalar tersebut dalam rangka untuk melihat pola pengaruh kejutan anggaran, baik yang terantisipasi maupun yang tidak terantisipasi, terhadap variabel moneter, yang dalam contoh ini adalah kurs rupiah. Konsep asa nalar yang merupakan koreksi terhadap asa yang adaptif pertama kali dikemukakan oleh Muth (lihat Holden, et.al., 1985). Muth mengatakan bahwa pelaku ekonomi membentuk asa nya berdasarkan teori ekonomi guna melakukan prediksi terhadap variabel ekonomi. Asa nalar pada dasarnya adalah prediksi teori dengan menggunakan segala 151 informasi yang tersedia pada waktu prediksi itu dilakukan. Asa nalar sering juga disebut dengan asa yang konsisten, sebab asa selalu konsisten dengan teori ekonomi yang mendasari. Diasumsikan jika pelaku ekonomi menggunakan seluruh informasi yang tersedia, maka pelaku ekonomi tidak akan melakukan kesalahan secara sistematis. Ada perbedaan mendasar dalam pembentukan asa nalar model Klasik Baru dan model Keynesian Baru (New Keynesian). Dalam model Klasik Baru diasumsikan bahwa pelaku ekonomi menghadapi pasar yang sempurna, sehingga terjadi market clearing di setiap pasar. Dalam model Keynesian Baru dimungkinkan adanya ketidakseimbangan dalam salah satu pasar, namun pelaku ekonomi mengetahui secara sempurna adanya ketidakseimbangan dan ketidak-sempurnaan pasar itu. Pelaku ekonomi menggunakan informasi mengenai ketidak-sempurnaan pasar itu untuk pembentukan asa nalar. Menurut Cooper dan John (1991) dan Bryant (1991) dimungkinkan adanya koordinasi dalam kegagalan koordinasi dan kegagalan pasar. Model asa nalar mempunyai tiga sifat penting yang berhubungan dengan rata-rata error term, varian dari error, serta hubungan antarkesalahan prediksi untuk waktu yang berbeda (Holden, et.al., 1985). Pertama, model asa nalar mensyaratkan bahwa error term haruslah mempunyai rata-rata nol dan tidak terdapat outokorelasi. Syarat itu sangat penting, sebab perlu disadari bahwa error term tidak selalu bernilai nol. Walaupun menggunakan asa nalar, pelaku ekonomi dapat pula melakukan kesalahan prediksi, namun kesalahan itu tidak akan bersifat sistematis. Error term bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Ketika kesalahan telah diketahui, kesalahan itu tidak akan mempengaruhi asa di masa yang akan datang, karena kesalahan itu bersifat acak. Kesalahan tidak akan mempengaruhi asa di masa yang akan datang, jika tidak terdapat informasi baru yang mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi. Kenyataan itu tentu berbeda dengan yang terjadi dengan asa yang bersifat adaptif. Dalam pembentukan asa yang adaptif, kesalahan di masa lalu akan mempengaruhi pembentukan asa di masa yang akan datang. Karena nilai asa dari kesalahan baku (Ht+1) harus sama dengan 152 nol, atau sering juga disebut harus resik suara (white noise), maka E(yt+1) merupakan prediktor yang tidak bias terhadap yt+1. Secara umum dapat dikatakan bahwa asa nalar terhadap suatu variabel akan mempunyai sifat yang tidak bias. Sifat yang kedua, model asa nalar dapat juga disebut sebagai prediktor yang efisien terhadap yt+1. Pernyataan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa varian dari kesalahan prediksi dari asa nalar terkecil diantara berbagai kemungkinan prediktor. Hal tersebut dimungkinkan karena error term, Ht+1, bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan error term pada periode sebelumnya, karena tidak ada informasi baru pada waktu asa tadi terbentuk yang dapat membantu untuk memprediksi et+1. Sifat yang ketiga dari model asa nalar adalah bahwa hubungan antara kesalahan prediksi antarwaktu akan berkorelasi. Sering dikatakan bahwa asa nalar mempunyai konsekuensi bahwa kesalahan peramalan berotokorelasi (serially correlated). Korelasi antarkesalahan peramalan itu hanya terjadi pada satu periode ke depan (first order serial correlation). Namun kesalahan peramalan tidak akan berkorelasi dengan informasi yang tersedia pada saat asa terbentuk. Sebab jika ada korelasi antara keduanya, maka informasi dapat digunakan untuk meningkatkan peramalan, sehingga peramalan aslinya tidak lagi efisien. Jika korelasi antara kesalahan peramalan dengan informasi yang tersedia, maka peramalan model asa menjadi tidak efisien lagi, sehingga sifat itu akan bertentangan dengan sifat kedua. Ketiga sifat di atas membedakan antara asa nalar dengan asa yang adaptif. Ada tiga perbedaan nyata antara asa nalar dengan asa yang adaptif. Pertama asa nalar lebih menekankan pada terbentuknya asa ke depan (forward looking expectations), sedangkan asa yang adaptif lebih menekankan pada penggunaan mekanisme ekstrapolasi trend masa lampau. Perbedaan kedua adalah bahwa dalam asa nalar pelaku ekonomi selalu berperilaku optimal. Pelaku ekonomi menggunakan seluruh informasi yang ada, baik informasi masa lampau, informasi yang sedang berlangsung, maupun informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perbedaan ketiga ialah bahwa model asa nalar 153 lebih mengandalkan teori ekonomi dalam pembentukan asa, sedangkan asa yang adaptif lebih bersifat deterministis. Ada berbagai metode untuk solusi model asa nalar, diantaranya adalah metode iterasi atau reduced form, Muthian, dan Lucas (Holden, et.al, 1985). Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode reduced form. Ada tiga langkah yang diperlukan untuk solusi reduce form ini. Pertama reduced form dari persamaan struktural harus ditemukan terlebih dahulu, dengan mengasumsikan variabel asa bersifat eksogen. Langkah kedua dikerjakan dengan melakukan solusi asa . Langkah terakhir solusi asa disubstitusikan kembali ke persamaan struktural. Yang disebut dengan persamaan reduced form adalah persamaan yang sisi sebelah kanan persamaan (variabel independen) semuanya terdiri dari variabel eksogen (Pindyck, 1998). Untuk menurunkan persamaan reduced form dari persamaan struktural, berarti harus dibedakan terlebih dahulu mana variabel endogen dan variabel eksogen dari persamaan struktural. Untuk dapat membedakan antara variabel endogen dan eksogen perlulah persamaan struktural ditulis kembali: Persamaan struktural yang ditulis disini adalah persamaan struktural jangka panjang, yang mengandaikan pelaku ekonomi mempunyai informasi yang sempurna (perfect foresight). Pelaku ekonomi (pemerintah, rumah tangga, dan swasta) mengalami ketidak pastian dalam variabel pendapatan di masa yang akan datang (Eat+1), Investasi di masa yang akan datang (EIt+1), dan kurs di masa yang akan datang (Eet+1). Persamaan struktural itu secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Permintaan konsumsi ct, dari persamaan (19) ct =D 10 + D11 it + D12 at + D13 Eat+1 + e10 Permintaan impor dari persamaan (20) mt = D20 + D21 (e+pm-pa) + D22 at + e20 Permintaan investasi, It = D30 + D31 i + D32 at + D33 E It+1 + e30 Keseimbangan Pasar Uang, it = D41 at + D42 E at+1 + D43 mont + u2 154 Paritas Suku Bunga, et = D51 rf + D52 it + D53 E et+1 + e7 Kurva Phillips, pt-pt-1 = D61 (outg) + D62 et + ut Penerimaan Pemerintah, txt = D70 + D71 oilpt + D72 yt + D73 txt-1 + u7 Belanja Pemerintah, gt = D80 + D81 et + D82 yt + D83 gt-1 + u6 Hubungan antara defisit anggaran dengan uang beredar, Δmont = D93 (gt – txt) Defisit anggaran, def = (g-tx) + insdef Mekanisme transmisi dari kejutan anggaran terhadap perekonomian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika pemerintah melakukan kejutan anggaran (kebijakan yang melawan perekonomian - against the wind), maka melalui proses pendanaan defisit, kejutan anggaran akan mempengaruhi uang inti dan selanjutnya jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar akan mempengaruhi suku bunga, dan selanjutnya akan mempengaruhi di satu sisi langsung mempengaruhi kurs dan kurs yang diharapkan di sisi lain akan mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, impor, dan juga berpengaruh balik pada pengeluaran pemerintah, yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat harga, kurs, dan kurs yang diharapkan. Melalui ketidak pastian kurs ini masyarakat mengantisipasi kebijakan defisit anggaran, sehingga jika seluruh masyarakat mempunyai informasi secara sempurna, kebijakan pemerintah itu dapat menjadi tidak efektif. Untuk mendapatkan solusi dinamis dari variabel asa nalar dengan metode reduced form itu dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama 155 diperoleh reduced form dengan mengasumsikan variabel asa nalar sebagai variabel eksogen. Selanjutnya melalui proses iterasi baik forward maupun backward dapar diperoleh solusi dinamis variabel asa nalar. Solusi dinamis variabel asa nalar tersebut secara umum dapat dituliskan sebagai berikut; di mana koefisien Di, dan E merupakan komposit dari koefisien persamaan struktural. Jika diasumsikan bahwa setiap variabel eksogen tercipta melalui proses yang auto-regresif, yakni seperti Oilpt = D0 + D1Oilpt-1 + D2 Oilpt-2........... + Dn Oilpt-n + e1, (22) maka persamaan (21) dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. et = D0 + D1 oilpt-i + D2 r*t-i + D3 p*t-i + D4 yst-i + D5 insdeft-i + e2 (23) 156 157 Keterangan gambar dan persamaan: CSPNL_M = ct YDINL = at = Pendapatan yang siap dibelanjakan MGSNL = mt EXRPL = et = Kurs rupiah CPICPI = pm = Indeks harga konsumen negara-negara industri CPI = pat = Indeks harga konsumen dalam negeri INPNL_M = It = Investasi dalam negari RRRPL = i = Suku bunga domestik EINPNLF7 = E It+1 = Investasi masa yang akan datang yang diharapkan EYDINLF7 = E at+1 = Pendapatan yang siap dibelanjakan yang diharapkan MONNS = mont = Jumlah uang beredar EEXRPLF7 = E et+1 = Kurs yang diharapkan GDPNL = yt YS = Output potensial TXREV_M = txt OILPL = oilpt = Harga minyak dunia SPENL_M = gt DEFNL= def = Defisit anggaran BDENL_M-NTXNL = Konsumsi rumah tangga = Impor barang dan jasa terhadap dolar = Pendapatan Nasional Bruto = Penerimaan pemerintah (struktural) dari pajak = Belanja pemerintah yang struktural = insdef = Instrumen defisit anggaran BDENL_M = Belanja pemerintah yang dapat dikontrol pemerintah (discretionary fiscal policy), sebagai instrumen NTXNL = Penerimaan pemerintah yang dapat dikontrol pemerintah (discretionary fiscal policy), sebagai instrumen 158 Keterangan Simbol dalam Gambar Simbol Keterangan Variabel yang terbentuk dalam persamaan identitas Variabel instumen yang digunakan sebagai alat kebijakan Variabel yang terbentuk dalam persamaan perilaku (behavioural equation) Variabel eksogen Tanda penghubung, jika banyak variabel mempengaruhi satu variabel tertentu secara bersama. Hasil Penelitian dan Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedikit atau banyak kebijakan defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, kurs, dan tingkat harga (inflasi). Sesuai dengan pembelaan Barro (1989) yang menyatakan bahwa tidak semua orang tua punya anak, tetapi semua anak pasti punya orang tua. Sedikit atau banyak pasti terjadi hubungan antargenerasi. Jika hubungan antargenerasi tidak sepenuhnya erat, kebijakan defisit anggaran akan efektif walaupun tidak sepenuhnya efisien. Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan defisit anggaran, karena kebijakan defisit anggaran bukan tanpa biaya. Efisiensi kebijakan defisit anggaran perlu dicermati. Ada hubungan timbal balik antara kebijakan defisit anggaran dan variabel moneter. Kebijakan fiskal mempengaruhi instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempengaruhi instrumen kebijakan fiskal. 159 Hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter bersifat saling menetralkan dampak ekonomi yang dihasilkan. Jika dampak moneter defisit anggaran bersifat ekspansif, maka dampak ekspansi moneter akan bersifat kontraktif. Independensi Bank Sentral justru menuntut koordinasi antara penguasa fiskal dan penguasa moneter lebih erat, dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan pengendalian stabilitas moneter khususnya. Persamaan-persamaan dalam model mampu mereplikasi fluktuasi data dengan baik (lampiran gambar). Seperti telah diprediksikan secara teoritik kemampuan model mereplikasi fluktuasi data disebabkan selain oleh sahihnya teori yang mendasarinya juga oleh penyertaan variabel kejutan, asa nalar, dan Model Koreksi Kesalahan. Pengukuran statistik RMS Percent Error dan U’Theil Inequality Coefficient menunjukkan hasil yang sangat bagus. Pengukuran statistik yang pertama yang menunjukan hasil yang bagus menyatakan bahwa perbedaan antara data aktual dan nilai prediksi yang dihasilkan model sangat kecil. Pengukuran statistik yang kedua yang menunjukkan hasil yang bagus menyatakan bahwa nilai prediksi yang dihasilkan model mampu mengikuti titik belok data aktual. Para pelaku ekonomi dalam melakukan keputusan ekonomi, selain mempertimbangkan yang aktual terjadi di lapangan, juga menggunakan asa nalar. Asa nalar tersebut mencerminkan peristiwa yang mereka harapkan terjadi di masa yang akan datang. Kesimpulan tersebut didukung oleh uji statistik yang menunjukkan bahwa variabel asa nalar, baik yang tersirat dalam model struktural, maupun dalam uji asa nalar, signifikan berperanan dalam menentukan variabel dependen. Dengan asa nalar pelaku ekonomi sangat reaktif terhadap ketidaksesuaian antara informasi awal yang dijanjikan pemerintah dan peristiwa aktual yang mereka alami. Mereka akan bereaksi negatif terhadap ketidaksesuaian itu. Para pengusaha paling reaktif terhadap ketidaksesuaian informasi tersebut. Penguasa fiskal dan moneter harus semakin transparan dalam meluncurkan berbagai kebijakan ekonominya, agar para pelaku ekonomi lebih cepat belajar dari informasi yang mereka terima. Berbekal informasi yang akurat dan transparan 160 tersebut diharapkan pelaku ekonomi akan bertindak sesuai dengan sasaran kebijakan yang diinginkan penguasa moneter dan fiskal, sehingga proses belajar dari pengalaman menjadi murah. 161 Referensi _______, “Inflationary Finance and the Dynamics of Inflation: Indonesia 1951-72”, American Economic Review, Vol. 67, June, 1977, 390403. Agenor, Pierre-Richard, dan Peter J. Montiel, Development Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996. Aghevli, Bijan B., dan Mohsin S. Khan, “Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries”, IMF Staff Paper, Vol.25, No.3, September 1978: 383-416. Adji, Arti, Is Public Debt Neutral? Evidence For Indonesia, Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia(JEBI), September 1995, 21-32. Barro, Robert J, “The Ricardian Approach to Budget Deficits”, Journal of Economic Perspectives, Vol.3, No.2, Spring 1989, 37-54. Barro, Robert J., “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political Economics, No. 82 November/December 1974, 1095-1117. Begg, David K.H., “The Rational Expectations Revolution in Macroeconomics, Theories and Evidence”, John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1985. Bernheim, B.Douglas, “A Neoclassical Perspective on Budget Deficits”, Journal of Economics Perspectives, Vol. 3, No. 2, Spring 1989, 5572. Binger, Brian R. and Elizabeth Hoffman, Microeconomics with Calculus, Scott, Foresman and Company, United of America, 1988. Blejer, Mario, I., and Adrienne Cheasty, “The Measurement of Fiscal Deficits: Analytical and Methodological Issues”, Journal of Economic Literature (JEL), Vol. XXIX, December 1991, 1644-1678. Boediono, Teori Moneter; Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5, BPFE, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1983. Boskin, J Michael, “What Do We Know About Consumption and Saving, and What are The Implications For Fiscal Policy?”, American Economic Review and Proceedings, Vol.78, No. 2, 1978, 401-407. 162 Brown, T.M., Specification and Uses of Econometric Models, New York: Macmillan, 1970. Bryant, John, “ A Simple Rational-Expectations Keynes-Type Model”, in Gregory Mankiw dan David Romer, eds, New Keynesian Economics: Coordination Failures and Real Rigidities, Vol.2, N., The MIT Press, Cambridge, London, 1995. Cagan, Phillip, “The Monetary Dynamics of Hyperinflation.” In Studies in the Quantity Theory of Money, ed. By Milton Friedman, University of Chicago Press, 1956. Chacholiades, Miltiades, International Economics, McGraw-Hill, New York, 1990. Chiang, Alpha, C., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3rd Edition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1984. Cooper, Russel and Andrew John, “Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models, in New Keynesian Economics: Coordination Failures and Real Rigidities, Vol.2, N. Gregory Mankiw dan David Romer, eds, The MIT Press, Cambridge, London, 1995. Davidson, J.D., Hendry, F. Srba and S. Yeo, “Econometric Modelling of the Aggregate Time-Series Relationship between Consumers’ Expenditure and Income in the United Kingdom”, Economic Journal, vol. 88, 1978, 661-692. De Grouwe, Paul, Macroeconomic Theory for The Open Economy, Gower Publishing Company Limited, Hampshire, England, 1983. De Haan, Jacob, dan Jan Egbert Storm, “ Do Financial Markets and the Maastricht Treaty Discipline Governments? New Evidence”, Applied Financial Economics (APF), ISSN 0960-3107, Vol 10 iss 2 April 2000, 221. Deaton, A., “Involuntary Saving Through Unanticipated Inflation”, American Economic Review, vol. 67, no. 5, 1977, 900-910. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, Gordon R.Sparks, Macroeconomics, 3rd edd., McGraw-Hill Ryerson Limited, Toronto, 1989. 163 Dutton, Dean S., “A Model of Self Generating Inflation: The Argentine Case”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol.. 3, Mei 1971, 245-262. Egwalkhide, Festus, O., “Effect of Budget Deficits on The current Account Balance in Nigeria: A Simulation Exercise”, The African Economic Research Consortion, The Regal Press Kenya, 1997. Eisner, Robert, “Budget Deficit: Rhetoric and Reality”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2, Spring 1989, 73-93. Engle, Robert F. and C.W.J. Granger, “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol.55, No.2, March, 1987, 251-76. Flavin, M., The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Future Income, Journal of Political Economic, No. 89, 1981, 974-1009. Friedman, M. and M.S. Khan, A Theory of the Consumption Function, Princeton: Princeton University Press. 1957. Galardo, J Lopez, “Budget Deficit and Full Employment”, Journal of Post Keynesian Economics, Summer 2000, Vol. 22, No. 4, 549-563. Ghiglino, Christian dan Karl Shell, “The Economic Effects of Restrictions on Government Budget Deficits” Journal of Economic Theory (JET), ISSN 0022-0531, Vol. 94, Iss:1, Sept 2000, 106. Goweke, Laszlo; “ Labour Taxation, Efficiency Wages and The Long Run”, Bulletin of Economic Research (BOE), ISSN 0307-3378, Vol 52 Iss;4 Oct 2000, 241. Gramlich, Edward, M., “Budget Deficits and National Saving: Are Politicians Exogenous?”, Journal of Economic Perspectives, Vol.3, No.2, Spring 1989, 23-35. Grossman, Herschel, I., “Rational Expectations, Business Cycles, and Government Behavior”, in Stanley Fischer, eds, Rational Expectations and Economic Policy, The University of Chicago Press, Chicago, 1980, 5-22. Gujarati, Domodar, N., Basic Econometrics, 3rd edd., McGraw-Hill International Editions, 1995. 164 Hall, S.G., S.G.B. Henry, Macroeconomic Modelling, Bank of England, London, UK, 1988. Hayashi, Fumio, “Tests for Liquidity Constraints: a Critical Survey and some New Observation”, in Bewley, Truman F, ed., Advances in Econometrics, Fifth World Congress, Cambridge: Cambridge University Press, 1987. Holden, K., D.A.Peel, dan J.L.Thompsons, Expectations: Theory and Evidence, St.Matin’s Press, New York, 1985. Howard, Anton, and Chris Rorres, “Elementary Linear Algebra, Applications Version”, 8th edd, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000. IBII, Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2000; Berdasarkan Perhitungan Macromodel, Lembaga Penelitian Ekonomi Indonesia-IBII, Jakarta, 2000. Insukindro, “Pembentukan Model Dalam Penelitian Empirik Dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan”, Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI), Vol. 14 No.1, 1999, 1-8. Insukindro, Ekonomi Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman di Indonesia, BPFE, Jogjakarta, 1993 Insukindro, “Regresi Linier Lancung dalam Analisis Ekonomi: Suatu Tinjauan dengan Satu Studi Kasus di Indonesia”, Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 5, 1991, 75-88. Jehle, Geoffrey, A., Advanced Microeconomic Theory, Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs, New York, 1991. Khan, Mohsin, S., “The Variability of Expectation in Hyperinflations” Journal of Political Economy, Vol.85, Agustus 1977, 817-827. Kotlikoff, Laurence J., “Intergenerational Transfers and Savings”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, Spring 1988, 41-58. Lucas, R.E., Jr. “Econometric Policy Evaluation: A Critique”, in K. Brunner and A. Meltzer (eds), The Phillips Curve and Labor Markets, Amsterdam: North Holland, Carnegie-Rochester Series on Public Policy, 1976. 165 Mankiw, Gregory N., Macroeconomics, 3rd edition, Worth Publishers, New York, 1992. Mansur, Ahsan H, “Effect of a Budget Deficit on the Current Account Balance: The Case of the Philippines”, in Blejer, M.I. and K.Chu eds, Fiscal Policy Stabilization and Growth in Developing Countries, Washington , D.C. : International Monetery Fund, 1989. Maryatmo, Rogatianus, “The Role of Oil in Indonesian Economy: A Case of Causality Test”, Modus, Edisi 06, 1994, 37-44. McCafferty, Stephen, Macroeconomic Theory, Harper & Row Publishers, New York, 1990. Pindyck, Robert S., Daniel L. Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasting, 4rd Edition., McGraw-Hill, New York, 1998. Price, Simon, and Insukindro, “The Demand for Indonesian Narrow Money: Long-run Equilibrium, Error Correction and Forward-Looking Behaviour”, The Journal of International Trade & Economic Development 3 (2) July 1994, 147-163. Repse, Einors, “Latvia: Focus on Country Development”, Finance & Development (FID), ISSN 0015-1947, Vol. 37 Iss:3, September 2000, 17. Romer, David, Advanced Macroeconomics, International Edition, 2nd edd., McGraw-Hill Higher Education, Singapore, 2001. Saleh, Samsubar, “Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia”, Disertasi S3, Universitas Gajah Mada Jogjakarta, tidak dipublikasikan, 2002. Sargent, Thomas J., and Neil Wallace, “Rational Expectation and the Dynamics of Hyperinflation”, International Economic Review, Vol 14, June 1973, 328-350. Sargent, Thomas, J., Macroeconomics Theory, 2nd Edition., Academic Press, Inc., New York, 1987. Seater, John J., “Ricardian Equivalence”, Journal of Economic Literature (JEL), Vol XXXI, March, 1993, 142-190. 166 Snowdown, B., and Vane H.R., A Modern Guide to Macroeconomics; An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, Gower House, United Kingdom, 1995. Thomas, R.L., Modern Econometrics; an Introduction, 1st Edition., Addison Wesley Longman, 1997. Wiles, Mark, H., “Harapan Rasional Sebagai Kontrarevolusi”, dalam buku Daniel Bell dan Irving Kristol (editor), Krisis Teori Ekonomi, LP3ES, Jakarta, 1987. Woo, W.T., Glassburner B., and Nasution A., Macroenomomic Policies, Crisis, and Long-Term Growth in Indonesia 1965-90, The World Bank, Washington, DC, 1994. Woodford, Michael, “Revolution and Evolution in Twentieth-Century Macroeconomics”, Paper Prepared for the Conference on “Frontiers of The Mind in the Twenty-First Century” Library of Congress, Washington, June 14-18, 1999. World Bank, Entering the 21st Century, World Development Report 1999/2000 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia; Indonesian Financial Statistics, 1983-2002. 167 Lampiran: Gambar Hasil Prediksi Yang Dihasilkan Model Penelitian dan Data Aktual Suku Bunga, Kurs, dan Tingkat Harga Gambar 1. Suku Bunga Aktual (RRRPL) dan Nilai Prediksi Suku Bunga (R6_RRRPL) Gambar 2. Nilai Prediksi (R6_CPI) dan Nilai Aktual Tingkat Harga (CPI) 168 Gambar 3. Nilai Prediksi (R6_EXRPL) dan Nilai Aktual Nilai Tukar Mata Uang Rupiah (Rp/$) 169 170 INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL: DOMINASI ATAU KAUSALITAS?1 Angelina Ika Rahutami Latar Belakang P erekonomian selalu bergerak secara simultan, sehingga penerapan suatu kebijakan tidak dapat disetrilisasi dari penerepan kebijakan yang lain. Ketika kebijakan yang ada berinteraksi, maka akan muncul perdebatan, sebenarnya kebijakan apa yang menjadi pemimpin, pengikut atau terjadi interaksi kausalitas. Dua blok perekonomian yang kerap mendapat sorotan di Indonesia adalah Blok Moneter dan Blok Fiskal. Pengambilan kebijakan di salah satu blok akan mempengaruhi kinerja blok yang lain. Hasil akhir kebijakan moneter maupun fiskal sebenarnya tergantung pada dominasi yang ditimbulkan oleh masingmasing kebijakan. Sargent dan Wallace (1981) membedakan pola pelaksanaan kebijakan dengan istilah kebijakan moneter dominan dan kebijakan fiskal dominan2. Kebijakan dikatakan kebijakan moneter dominan apabila otoritas moneter bersifat aktif dalam menentukan stok uang nominal atau suku bunga nominal, sedangkan kebijakan fiskal dominan ditandai dengan kebijakan moneter yang bersifat subordinat terhadap kebijakan fiskal dan dibebani pembiayaan defisit fiskal melalui pajak inflasi. 1 2 Merupakan pengembangan dari bagian disertasi S3 penulis Dalam konteks yang sama, Aiyagari-Gertler (1985) membedakan menjadi Rejim Ricardian dan Non-Ricardian, sedangkan Leeper (1991) menyebutnya dengan kebijakan moneter aktif (fiskal pasif ) dan kebijakan fiskal aktif (moneter pasif ) 171 Dalam analisis tradisional, koordinasi atau interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak menimbulkan masalah apabila dikontrol oleh pembuat kebijakan yang sama. Analisis ini akan mengalami perubahan bila pembuat kebijakan moneter dan fiskal adalah institusi yang berbeda karena kemungkinan besar akan terjadi dominasi atau ketidaksinkronan dalam interaksi antar otoritas. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa otoritas moneter dan fiskal berada di bawah institusi yang berbeda jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara yang memiliki otoritas moneter dan fiskal dalam satu lembaga yang sama (Bohn, 2002). Di Indonesia, otoritas fiskal berbeda dengan otoritas moneter. Otoritas fiskal adalah Departemen Keuangan, sedangkan otoritas moneter adalah Bank Indonesia (BI). Salah satu tugas otoritas fiskal adalah menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pada awal tahun (ex-ante) dengan melihat perkembangan berbagai indikator ekonomi makro (Departemen Keuangan, 2002: 15) berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia. Di lain pihak, karakteristik kebijakan sektor moneter di bawah otorisasi BI menunjukkan kecenderungan bahwa sektor moneter bukanlah sektor yang pasif3. Kebijakan-kebijakan moneter yang diambil tidak hanya semata-mata ditujukan untuk mempertahankan kondisi anggaran pemerintah, namun juga untuk kepentingan stabilisasi sektor moneter dan perekonomian secara keseluruhan. 3 Indikasi bahwa sektor moneter merupakan sektor yang aktif dapat dilihat dari hasil penelitian Goeltom (2005) mengenai kebijakan moneter. 172 Tabel 1 Periodisasi dan Evaluasi Kebijakan Moneter Periode Kebijakan moneter Evaluasi berdasarkan optimal policy rule Suku bunga Uang inti Cenderung ketat Cenderung ketat Cukup optimal Cenderung ekspansioner 19801982 Deregulasi dan liberalisasi finansial 19831984 Penguatan perbankan dan pertumbuhan ekonomi 19851987 Diskresi akibat tekanan BOP Cukup optimal pada 85/86, tapi terlalu longgar pada 86/87 Cukup optimal 19881989 Kebijakan ekspansif Terlalu longgar Cukup optimal, tapi terlalu ketat pada 88.4/89.3 19901992 Kebijakan uang ketat, kebijakan perbankan Terlalu ketat Terlalu longgar pada 90/91, terlalu ketat pada 91/92 19931994 Kebijakan dalam kondisi Cukup optimal yang cukup stabil Cukup optimal 19951997.2 Diskresi akibat inflasi dan permintaan domestik Terlalu longgar Terlalu ketat pada 1995, Cukup optimal pada 1996 1997.31999 Kebijakan krisis ekonomi Terlalu ketat Terlalu longgar pada 1998 20002003 Kebijakan jaga stabilitas untuk pemulihan ekonomi Terlalu longgar 2000/01, tapi cukup optimal pada 2002/03 Cukup optimal pada 2000/01, terlalu ketat pada 2002/03 Sumber : Goeltom, 2005. 173 Data evaluasi kebijakan moneter dan data awal perilaku variabel moneter menunjukkan bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang cukup tajam secara instrumen, tujuan maupun kelembagaan. Perubahan kebijakan yang paling menonjol adalah penggunaan kebijakan kaidah (policy rule) dan penargetan inflasi. Perubahan instrumen, tujuan maupun kelembagaan otoritas moneter diduga akan mengakibatkan perubahan struktural pada variabel-variabel ekonomi lain yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kondisi anggaran pemerintah. Kondisi ini tentunya akan membawa perubahan dalam interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bermaksud untuk menelusuri posisi kebijakan moneter dalam interaksi kebijakan secara teoritis dan melihat dan menganalisis indikator-indikator yang terkait dengan interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Posisi Kebijakan Moneter dalam Interaksi Kebijakan dalam Pemikiran Keynesian Baru Konsep Keynesian Baru4 merupakan konsep yang mewakili fenomena ketidakseimbangan ekonomi Indonesia dan kebijakan moneter yang dipilih oleh Bank Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi Indonesia ditunjukkan antara lain oleh penelitian Harmanta dan Ekananda (2005) tentang pasar kredit, Siregar dan Ward (2002) mengenai efek dominan kejutan sisi permintaan agregat terhadap fluktuasi ekonomi, dan penelitian Solikin (2004) mengenai fenomena kurva Phillips New Keynesian di Indonesia. Sedangkan penargetan inflasi seperti tertuang dalam UU No. 23 tahun 1999 merupakan kebijakan yang membutuhkan fungsi reaksi suku bunga (Taylor Rule) yang bersifat forward looking. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan penggunaan konsep Keynesian Baru dalam mengelola ekonomi. 4 Konsep Keynesian Baru secara ringkas berbicara mengenai pasar yang tidak sempurna, kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium), kekakuan upah dan harga, serta perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan kaidah. 174 Pemikiran Keynesian Baru dengan jelas menunjukkan bahwa kebijakan moneter memegang peran penting dalam menstabilkan ekonomi. Dalam dunia nyata penerapan kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya terutama kebijakan fiskal. Keterkaitan antar kebijakan memiliki implikasi bahwa kebijakan satu dengan yang lain dapat saling mendukung atau justru saling memperlemah. Secara tradisional interaksi kebijakan moneter dan fiskal dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu perilaku kebijakan aktif dan pasif. Sebetulnya penyebutan istilah kebijakan aktif dan pasif telah dimulai dari tahun 1981, dengan definisi yang berbeda. Sargent dan Wallace (1981) membagi jenis kebijakan menjadi moneter dominan dan fiskal dominan. Aiyagari dan Gertler (1985) lebih menggunakan terminologi rejim Ricardian dan Non-Ricardian, sedangkan Leeper (1991) cenderung menggunakan istilah kebijakan aktif dan pasif. .HELMDNDQPRQHWHUDNWLI .HELMDNDQPRQHWHUSDVLI .HELMDNDQ ¿VNDODNWLI I 7LGDNDGDHNXLOLEULXP II (NXLOLEULXPXQLN1RQ 5LFDUGLDQ .HELMDNDQ ¿VNDOSDVLI IV III (NXLOLEULXPXQLN5LFDUGLDQ 7LGDNDGDHNXLOLEULXP Gambar 1 Kuadran Kombinasi Kebijakan Moneter-Fiskal Model Leeper Pada dasarnya kebijakan aktif dan pasif berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Otoritas aktif tidak memberikan perhatian pada utang pemerintah dan bebas untuk menetapkan variabel kontrol, sedangkan otoritas pasif memberikan respons terhadap kejutan utang pemerintah. Salah satu implikasi dari konsep Keynesian Baru adalah kebijakan moneter lebih mampu menstabilkan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Ketika kebijakan moneter digunakan sebagai kebijakan yang akan menstabilkan fluktuasi ekonomi, maka hal yang penting untuk 175 dipahami adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah suatu proses bagaimana kebijakan moneter untuk merubah GDP riil dan inflasi. Keynesian Baru lebih banyak menggunakan pendekatan paradigma uang pasif. Paradigma uang pasif menggunakan suku bunga sebagai instrumen moneter, sasaran operasional berupa suku bunga jangka pendek dan nilai tukar, dan target akhir stabilitas harga. Kesenjangan output merupakan kausal dalam mekanisme transmisi. Perkembangan likuiditas dari waktu ke waktu hanya menyesuaikan diri secara pasif terhadap besaran permintaan dan inflasi. Keynesian Baru juga menyatakan bahwa penggunaan kebijakan yang bersifat kaidah jauh lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat diskresi. Salah satu implikasi kebijakan moneter Keynesian Baru dan sistem dominasi moneter menghendaki adanya independensi bank sentral. Independensi kebijakan menunjukkan adanya ruang gerak bank sentral yang bebas dari pertimbangan politik dan campur tangan orang lain dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter (Mustacelli dkk, 2000). Kondisi ini mengakibatkan, semakin independen bank sentral, semakin terbatas kemampuan pemerintah untuk memanipulasi kebijakan moneter bagi tujuan jangka pendek mereka, serta membatasi fleksibilitas kebijakan pemerintah atau kemampuan untuk bereaksi terhadap kondisi yang tidak diantisipasi atau tidak diinginkan (Bernhard, 1998). Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal Sebagian besar masalah mendasar dalam interaksi kebijakan moneter dan fiskal berkaitan dengan perbedaan aktivitas fiskal dan moneter, karena secara alami otoritas fiskal dan moneter merupakan entitas yang berbeda dengan instrumen, tujuan dan preferensi yang berbeda, (Fry, 1995:399). Interaksi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun dibutuhkan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal. Masalah ketidakjelasan penugasan, kedudukan bank sentral, perbedaan persepsi pimpinan, per176 bedaan instrumen yang digunakan, serta perbedaan otoritas menjadi sumber inkoordinasi moneter dan fiskal (Marszalek, 2003, Djojosubroto, 2004). Penelitian terdahulu mengenai interaksi kebijakan moneter dan fiskal dapat dibedakan menjadi 3 hasil utama. Sekelompok peneliti melihat bahwa interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak pernah bersifat satu arah atau bersifat kausalitas Kebijakan moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal dan demikian juga sebaliknya karena pemerintah bertindak seperti agen swasta, yang menghadapi kendala anggaran. Aghevli dan Khan (1978) dan Adji (1995) menunjukkan bahwa arah hubungan antara defisit anggaran dan variabel moneter adalah timbal balik. Secara lebih spesifik Bhattacharya dan Haslag (1999) mengatakan bahwa kebijakan moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal dan demikian juga sebaliknya, karena pemerintah bertindak seperti agen swasta yang menghadapi kendala anggaran. Tindakan moneter dan fiskal berinteraksi dalam satu kendala anggaran pemerintah yang sama. Hasil penelitian Maryatmo (2004) menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel moneter memiliki hubungan timbal balik dengan defisit anggaran. Suku bunga tidak mempengaruhi defisit anggaran, tetapi kurs dan harga mempengaruhi defisit anggaran. Di lain pihak defisit anggaran tidak mempengaruhi kurs dan tingkat harga, namun mempengaruhi suku bunga. Kelompok peneliti yang melihat bahwa sebetulnya kebijakan moneterlah yang akan mempengaruhi kondisi fiskal juga cukup banyak. Pergeseran kebijakan moneter memiliki efek yang penting bagi pemerintah dan tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini bank sentral memiliki komitmen baru terhadap inflasi yang rendah (Shapiro, 2004). Fenomena ini akan mempengaruhi pendapatan dari penciptaan uang (seigniorage) sehingga perlu dilakukan penyesuaian kesimbangan fiskal pada masa yang akan datang melalui kenaikan pajak atau penurunan pengeluaran (Nikitin dan Russell, 2004). Penelitian Farhadian dan Dunn (1986), Bennett dan Loayza (2000), serta Gros (2003) juga menunjukkan bahwa kenaikan preferensi anti177 inflasi bank sentral mendorong defisit publik primer yang lebih tinggi. Hasil simulasi stokastik Hostland (2001) menunjukkan bahwa semakin agresif kebijakan moneter akan menaikkan variabilitas suku bunga jangka pendek, tetapi akan menurunkan variabilitas output, inflasi dan biaya utang. Penelitian Dellas dan Slayer (2003) menemukan bahwa kebijakan moneter kaidah yang kontra siklis menyebabkan suku bunga riil yang lebih tinggi, tingkat pajak rata-rata yang lebih tinggi, output yang lebih rendah, variabilitas tingkat pajak dan konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan yang pro siklis. Penelitian interaksi moneter-fiskal yang dilakukan oleh Sargent dan Wallace (1975) menyatakan bahwa defisit anggaran yang didanai melalui sistem perbankan (bank sentral), akan mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar, dan selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan harga, yang berarti, pembiayaann defisit anggaran akan memiliki konsekuensi negatif ke tingkat harga (Marszalek, 2003, Moreno,2003). Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kebijakan moneter dalam berbagai cara, baik melalui dampak atas kredibilitas kebijakan moneter, efek jangka pendek pada permintaan, maupun melalui perubahan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi jangka panjang (Fialho dan Savino, 2002). Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Kausalitas5 Interaksi yang Kajian yang dilakukan oleh Rahutami (2007) menunjukkan bahwa interkasi kebijakan moneter dan fiskal bersifat kausalitas. Hasil estimasi blok moneter menunjukkan bahwa dalam jangka pendek jumlah uang beredar riil dipengaruhi secara positif oleh pendapatan nasional riil dan suku bunga. Depresiasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam 5 Diambil dari penelitian Rahutami (2007) yang menggunakan data sekunder triwulanan, mulai dari tahun 1980.1 sampai dengan tahun 2006.4. Model yang digunakan adalah model simultan dinamik yang dipecahkan dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS). Perilaku dinamik diamati dengan menggunakan model Error Correction Model (ECM) dua tahap Engel-Granger. Model penuh yang digunakan dalam penelitian Rahutami (2007) menggunakan lima (5) blok yaitu blok moneter, blok harga, blok fiskal, blok riil, dan blok eksternal. 178 jangka pendek, namun memberikan pengaruh yang negatif dalam jangka panjang. Hal ini memberikan indikasi bahwa masyarakat tidak memiliki kepercayaan yang cukup kuat terhadap Rupiah. Kebijakan moneter kaidah yang menjadi fokus dari penelitian ini juga menunjukkan berbagai hal menarik. Variabel inflasi, suku bunga periode sebelumnya maupun uang primer merupakan variabel yang mempengaruhi pembentukan suku bunga, dengan pengaruh yang lebih kuat pada informasi inflasi. Secara empiris dalam jangka pendek inflasi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh ekspektasi inflasi, inflasi periode sebelumnya, kesenjangan output, nilai tukar, ekspektasi pertumbuhan ekonomi riil dan perubahan struktur inflasi pada tahun 1998 akibat perubahan jangkar moneter. Sedangkan dalam jangka panjang, inflasi dipengaruhi secara signifikan oleh kesenjangan output dan nilai tukar. Bila melihat seluruh variabel yang dihipotesiskan akan mempengaruhi pembentukan inflasi ternyata memiliki pengaruh yang signifikan, maka pengelolaan inflasi membutuhkan kehati-hatian dan kredibilitas BI. Dengan kondisi ini, maka BI perlu lebih transparan, cermat dan kredibel dalam menyampaikan perkiraan inflasinya. Atau dengan kata lain kredibilitas BI dalam menyampaikan target inflasi menjadi suatu informasi penting yang akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan inflasi. Dengan model penargetan inflasi yang diterapkan oleh BI pada saat ini diharapkan kesalahan ekspektasi inflasi akan menjadi semakin kecil, sehingga masyarakat pun tidak mengalami kesalahan ekspektasi. Di sisi lain persamaan blok fiskal menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan nasional, harga minyak dunia dan obligasi luar negeri. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih ada ketergantungan terhadap penerimaan minyak dan gas, serta utang luar negeri. Dalam persamaan pengeluaran pemerintah diperoleh hasil bahwa depresiasi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, di samping pengaruh yang signifikan dari penerimaan pajak riil dan pendapatan nasional riil. Interaksi antara blok moneter dan fiskal terlihat pada signifikansi variabel kejutan. Bila dalam perilaku suku bunga terlihat bahwa kejutan 179 pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh yang signifikan, maka kejutan uang primer juga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah. Kejutan pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan suku bunga jangka pendek mengindikasikan bahwa perilaku BI belum sepenuhnya independen dan masih harus memberikan dana talangan bagi defisit anggaran. Implikasi dari kondisi ini adalah perilaku sektor fiskal tetap merupakan suatu tanda yang perlu direspon oleh BI sebagai otoritas moneter. Sedangkan kejutan uang primer juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini menunjukkan masih adanya keterkaitan antara sektor fiskal dengan sektor moneter meskipun sejak tahun 1999 telah terjadi perubahan hubungan, dan menjadi lebih independen. Deskripsi Indikator Moneter dan Keterkaitannya dengan Blok Fiskal Blok moneter merupakan aktivitas perekonomian dari sisi moneter dengan otoritas tertinggi di Bank Indonesia, sedangkan blok fiskal dalam suatu perekonomian lebih menggambarkan peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Blok moneter di Indonesia merupakan blok ekonomi yang relatif banyak mengalami perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan moneter di Indonesia terjadi baik dari sisi instrumen, target operasional, tujuan dan kelembagaan Bank Indonesia. Undang-undang Pokok Bank Indonesia pertama disahkan pada tanggal 19 Mei 1953 berisikan pembentukan BI yang pada awalnya berfungsi sebagai bank sirkulasi dan pada akhirnya menjadi bank sentral penuh. Tugas BI yang tercantum dalam UU Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953 adalah (i) menjaga stabilitas mata uang, (ii) menyelenggarakan peredaran mata uang, (iii) memajukan sistem perbankan, dan (iv) mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan. UU ini berlaku dari tahun 1953 sampai dengan 1967, dengan peran utama BI sebagai pencetak uang untuk kepentingan pemerintah (seignorage) yang pada akhirnya mendorong terjadinya inflasi yang sangat tinggi. 180 Perkembangan berikutnya adalah dikeluarkannya UU Bank Indonesia No.13 tahun 1968. BI memiliki peran sebagai stabilisator perekonomian melalui stabilisasi nilai tukar dan inflasi. Di samping itu selama tahun 1968 sampai dengan 1998, BI juga diberi tugas sebagai agen pembangunan dan memiliki peran penting dalam kredit sektor riil. Perubahan yang cukup besar dilakukan dengan disahkannya UU Bank Indonesia No. 23 tahun 1999. Berdasarkan UU ini, tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Pada awalnya BI diberikan independensi penuh dalam menentukan sasaran inflasi, sehingga dapat berbeda dengan asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun anggaran. Menurut UU BI No.23 tahun 1999, BI merupakan entitas publik yang independen yang memiliki otoritas penuh, dan bebas dari intervensi pemerintah. Perubahan kembali terjadi dengan dilakukannya amandemen terhadap UU BI tahun 1999 pada tahun 2004. Dalam amandemen UU BI ini, penetapan target inflasi dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan BI. Perubahan ini menunjukkan bahwa BI hanya memiliki independensi instrumen dan tidak lagi memiliki independensi tujuan. Kebijakan moneter yang terkait dengan stabilisasi harga memiliki jangkar nominal yang berbeda-beda. Pada awalnya nilai tukar dan besaran moneter digunakan sebagai jangkar nominal kebijakan moneter. Namun mulai tahun 1999 jangkar nominal diganti dengan suku bunga. Penargetan inflasi sendiri telah dilakukan sejak tahun 2000 walaupun belum dijangkarkan secara resmi, dan masih dalam proses pembelajaran. Sedangkan secara resmi untuk mendukung pelaksanaan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru, maka pada Juli 2005 BI mengimplementasikan Inflation Targeting Framework (ITF), yang mencakup empat elemen dasar yaitu (i) penggunaan suku bunga BI Rate, (ii) proses perumusan kebijakan moneter 181 yang antisipatif, (iii) strategi komunikasi yang lebih transparan, dan (iv) penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Walaupun ITF lebih memberikan fokus ke stabilitas harga, namun pada dasarnya BI tetap berupaya untuk menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan kebijakan, jangkar nominal dan juga sifat kelembagaan tercermin juga pada pergerakan variabel-variabel seperti suku bunga, dan inflasi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis suku bunga nominal yaitu PUAB, deposito berjangka 1 bulan sampai dengan 2 tahun, suku bunga kredit modal kerja, dan suku bunga kredit investasi. Suku bunga Indonesia selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga asing. Bahkan pada tahun 1997-1999 memiliki jarak yang relatif lebar dengan suku bunga asing. Kondisi ini dapat menyebabkan suku bunga Indonesia tidak menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Perkembangan suku bunga dalam negeri ditandai dengan beberapa hal penting. Pada tahun 1987, pemerintah menaikkan suku bunga SBI untuk mencegah terjadinya spekulasi. Kenaikan suku bunga SBI tertinggi tercapai pada tahun 1997, sehingga mencapai 70 persen. Kenaikan suku bunga SBI ini dimaksudkan untuk membatasi ekspansi kredit perbankan dan menarik uang beredar dari sistem perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI di BI. Akibat terjadinya bank run pada tahun 1997, maka pada 1998 kuartal 4 BI menaikkan suku bunga deposito tertinggi menjadi 52,32 persen dengan tujuan untuk menaikkan tingkat likuiditas bank. 182 Keterangan : id = suku bunga deposito, ik = suku bunga kredit, isbi= suku bunga sbi, if= suku bunga LIBOR, INF_Y = inflasi year on year Sumber: Bank Indonesia Gambar 2 Suku Bunga Domestik, Suku Bunga Luar Negeri, dan Inflasi 1990.1-2011.2 Tahun 1998-2000, semua suku bunga mengalami penurunan. Pada tahun 2001, suku bunga deposito naik lebih tinggi dibandingkan kenaikan suku bunga lain, sehingga menyebabkan pergeseran preferensi masyarakat dalam menempatkan dana. Kondisi ini dirasa tidak memperbaiki kondisi sektor perbankan, maka suku bunga ditekan agar menjadi semakin rendah, sehingga jarak dengan suku bunga luar negeri tidak terlalu tinggi. Suku bunga mengalami kenaikan lagi pada periode 2005-2006, dan mulai 2009 berhasil ditekan di bawah 10 persen. Gambar tersebut juga menunjukkan adanya pola yang sama antara inflasi dengan suku bunga SBI. Kenaikan inflasi akan diikuti oleh kenaikan suku bunga yang merupakan bentuk kebijakan moneter agar tidak terjadi ekspansi kredit yang berlebihan. Apabila tidak terjadi ekspansi kredit maka perekonomian diharapkan akan lebih stabil sehingga menekan terjadinya inflasi. Kebijakan uang ketat dengan cara menaikkan suku bunga di satu sisi dapat meredam terjadinya inflasi, namun di sisi lain, kebijakan ini dapat 183 mengorbankan sektor riil. Tingginya suku bunga kredit akan menyebabkan sektor riil tidak dapat mengembangkan usaha, tidak terjadi investasi baru, sehingga dunia usaha akan melemah. Blok kedua adalah blok fiskal. Perilaku blok fiskal ini dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan realisasinya. Pada rejim Orde Baru, kebijakan APBN menganut sistem berimbang (balanced budget), namun sejak tahun anggaran 2000, kebijakan APBN menganut sistem defisit (deficit budget) yang biasanya ditetapkan sekian persen dari PDB. Untuk menutup defisit anggaran tersebut pemerintah mengupayakan program pembiayaan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan sistem anggaran pada tahun 2000 berkaitan erat dengan perubahan kebijakan fiskal. Perubahan yang terjadi pada tahun 2000 tersebut dimulai dengan perubahan tahun anggaran menjadi tahun kalender, sehingga pada tahun 2000, jangka waktu anggaran adalah 1 April-31 Desember, dan untuk tahun-tahun berikutnya adalah 1 Januari-31 Desember. Perubahan berikutnya adalah cara penyajian APBN yang mengikuti standar internasional (Government finance statistics), dan penyusunan APBN yang dipengaruhi oleh semangat otonomi daerah. 184 Sumber : Departemen Keuangan RI Gambar 3 Nilai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah dan Proporsinya terhadap PDB, 1990.1-2010.4 Dari sisi penerimaan, mulai tahun 2000 terjadi kecenderungan peningkatan penerimaan negara dengan kontributor utama berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak, serta penerimaan hibah. Meskipun terjadi kenaikan penerimaan, namun proporsi penerimaan pemerintah terhadap PDB cenderung mengalami penurunan. Dari sisi pengeluaran pemerintah, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, pengeluaran pemerintah menunjukkan kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan pemerintah. Hal ini menyebabkan defisit anggaran yang semakin besar. Demikian juga dengan proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Interaksi antara kebijakan moneter dengan kondisi anggaran terlihat jelas pada gambar 6 berikut. Ketika inflasi tinggi, maka defisit anggaran akan semakin besar. Fenomena pada tahun 1998 sampai dengan 2000 merupakan pembuktian yang cukup kuat, ketika inflasi dapat ditekan akibat kebijakan moneter yang tepat, maka anggaran akan menjadi surplus. 185 Namun tampaknya pergerakan inflasi dari tahun 2003.4 sampai 2010.4 yang cenderung stabil di bawah 10%, tidak dapat memperbaiki kondisi defisit anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak cukup mampu untuk memperbaiki kondisi defisit anggaran pemerintah Sumber : Departemen Keuangan RI Keterangan: Defisit dalam grafik ini diperoleh dari penerimaan-pengeluaran Gambar 4 Nilai Defisit APBN Riil Dan Inflasi 1990.1-2010.4 Perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel moneter juga membawa dampak pada perubahan indikator ekonomi makro yang lain. Gambar 7 berikut menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto riil dengan inflasi (y-o-y). Penurunan PDB riil yang cukup tajam terjadi pada tahun 1998-1999. 186 Sumber : Bank Indonesia Gambar 5 PDB Riil Dan Pergerakan Inflasi 1990.1-2010.4 Pada tahun 1998 PDB riil mengalami penurunan sebesar 13,7 persen akibat lesunya kegiatan investasi dan konsumsi swasta. Penurunan kegiatan investasi ini berkaitan dengan memburuknya kondisi perbankan, rendahnya kepercayaan investor asing dan lemahnya permintaan konsumsi domestik. Penurunan konsumsi domestik terjadi akibat lemahnya daya beli masyarakat akibat terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Pola yang terlihat ketika inflasi mengalami kenaikan maka PDB riil akan cenderung mengalami penurunan atau bahkan pertumbuhan yang negatif akibat tekanan harga dan lemahnya daya beli. Ketika inflasi dapat dikelola dengan baik, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pun akan berjalan cenderung lebih stabil. Bila dibandingkan dengan kondisi anggaran pemerintah, maka terdapat indikasi bahwa kebijakan moneter lebih banyak memberikan pengaruh kepada PDB dibandingkan kepada anggaran pemerintah. 187 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian empiris, dan indikasi data yang ada di Indonesia, maka terlihat bahwa interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal bersifat kausalitas. Suku bunga dan uang primer merupakan dua variabel yang harus mendapat perhatian lebih dari Bank Indonesia karena berinteraksi secara kuat dengan anggaran pemerintah. Bank Indonesia juga harus tetap menjaga independensinya, dan tetap harus meningkatkan kredibilitas serta transparansinya, karena kebijakan moneter memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggaran pemerintah dan indikator makro yang lain. 188 Daftar Pustaka ___________ (2002), Bunga Rampai Kebijakan Fiskal, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI, Japan International Coorperation Agency, Jakarta, Agustus . ___________, Statistik Ekonomi dan Keuangan, Bank Indonesia, berbagai edisi. Adji, Arti (1995), “Is Public Debt Neutral? Evidence For Indonesia,” Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia (JEBI): 21-32, September. Aghevli, Bijan B., dan Mohsin S. Khan (1978), “Government Deficits And The Inflationary Process In Developing Countries,” IMF Staff Paper, Vol.25, No.3: 383-416, September. Aiyagari, S. Rao, dan Mark Gertler (1985), “The Backing of Government Bonds and Monetarism,” Journal of Monetary Economics 16: 19–44, July. Benett, Herman, dan Loayza N. (2000), “Policy Biases when The Monetary and Fiscal Authorities Have Different Objectives,” Central Bank of Chile Working Papers, No. 66: 1–41. Bhattacharya, Joydeep, dan Joseph H. Haslag (1999), “Monetary Policy Arithmetic: Some Recent Contributions,” Federal Reserve Bank Of Dallas Economic And Financial Review, Third Quarter: 26-36 Bohn, Frank (2002), “Public Finance Under Political Instability And Debt Conditionality,” University of Essex, Department of Economics Discussion Papers 540. Dellas, Harris, dan Kevin D Slayer (2003), “Some Fiscal Implications Of Monetary Policy,” Bulletin Of Economic Research 55:1: 21-36 Djojosubroto, Dono Iskandar (2004), “Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia”, Dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep Dan Implementasi, Eds. Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 189 Farhadian Z, Dunn R.M.Jr (1986), “Fiscal Policy And Financial Deepening In A Monetarist Model Of The BOP,” Kyklos Working Paper, 39: 66-84. Fialho, Marcelo Ladeira, dan Marcelo Savino (2002), “Monetary And Fiscal Policy Interactions In Brazil: An Application Of The Fiscal Theory Of The Price Level,” Portugalî Working Paper: 1-20. Fry, Maxwell J (1995), Money, Interest And Banking In Economic Development, 2nd Ed., The Johns Hopkins University Press, Baltimore. Goeltom, Miranda S. (2005), Perspectives On Implementing Time Consistency And Credibility In Monetary Policy: The Case Of Indonesia, Paper Presented At The International Conference On Marrying Time Consistence In Monetary Policy With Financial Stability: Strengthening Economic Growth”, Organized By Bank Indonesia, Denpasar-Bali, December 1-3. Gros, Daniel (2003), “Financial Aspects Of Central Bank Independence and Price Stability The Case of Turkey” CEPS-EDP project: 1-20. Harmanta, dan Ekananda, Mahyus (2005). “Disintermediasi Fungsi Perbankan Pascakrisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan: 51-78, Juni. Hostland, Doug (2001), “Monetary Policy And Medium-Term Fiscal Planning”, Department Of Finance Working Paper, 20. Leeper, Eric M. (1991), “Equilibria Under ‘Active’ And ‘Passive’ Monetary And Fiscal Policies”, Journal Of Monetary Economics, 27: 129-147 Marszałek, Paweł (2003), “Coordination Of Monetary And Fiscal Policy”, The Poznań University Of Economics Proceeding Paper, Volume 3 Number 2: 41-52. 190 Maryatmo, Rogatianus (2004), “Dampak Moneter Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah Dan Peranan Asa Nalar Dalam Simulasi Model Makroekonomi Indonesia (1983:1-2002:4)”, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan). Moreno, Ramon (2003), “Fiscal Issues And Central Banking In Emerging Economies: An Overview “, BIS Papers No 20:1-9, October. Nikitin, Maxim, dan Steven Russell (2004), “Monetary Policy Arithmetic: Reconciling Theory With Evidence”, Working Paper : 2:85,August. Rahutami, Angelina Ika (2007), “Interaksi Kebijakan Moneter Kaidah Dengan Anggaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 1980.1-2006.4: Pendekatan Sistem Ekonomi Simultan”, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan). Sargent, Thomas J., dan Neil Wallace (1981), “Some unpleasant monetarist arithmetic”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 5: 1–17, Fall. Shapiro, Matthew D. (2004), “Discussion Of Engen And Hubbard: Federal Government Debt And Interest Rates”, Artikel Dalam NBER Macroeconomics Annual Conference, April Siregar, Hermanto, dan Ward, Bert D (2002). ”Were Aggregate Demand Shocks Important in Explaining Indonesian Macroeconomic Fluctuations?”. Journal of the Asia Pacific Economy. Vol 7: 35-60. Solikin (2004). ”Kurva Philips dan Perubahan Struktural di Indonesia : Keberadaan, Pola Pembentukan Ekspektasi, dan Linieritas”. Buletin Ekonomi dan Perbankan: 41-75, Maret. 191 192 PERAN STIMULUS FISKAL DAN PELONGGARAN MONETER PADA PEREKONOMIAN INDONESIA SELAMA KRISIS FINANSIAL GLOBAL1 Iskandar Simorangkir2 Justina Adamanti3 Krisis keuangan global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2008 telah mengakibatkan penurunan tajam pertumbuhan ekonomi dunia dan bahkan hampir semua negara mengalami kontraksi ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi telah dilakukan untuk mengatasi kontraksi ekonomi tersebut. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melakukan stimulus fiscal,sementara di sisi kebijakan moneter, bank sentral menurunkan suku bunga yang cukup signifikan. Sejalan dengan negara lain, Indonesia juga melakukan kebijakan yang sama, yaitu menurunkan suku bunga dan meningkatkan stimulus fiskal. 1 Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Call for Papers - EcoMod2010, Istanbul, 7-10 Juli 2010 untuk komentarnya. Secara khusus ucapan terimakasih diucapkan kepada M. Barik Bataludin, Harmanta dan Endy Dwi Tjahjono, para ekonom di Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia untuk bantuan dan masukannya. Semua pendapat yang diutarakan dalam paper ini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan resmi dari Bank Indonesia. 2 Kepala Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, Indonesia; Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia; email: [email protected] (corresponding author). 3 Ekonom Junior di Biro Riset Ekonomi, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, Indonesia; email: [email protected] 193 Paper ini akan mengkaji dampak stimulus fiskal dan penurunan suku bunga terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan financial computable general equilibrium. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, kombinasi kebijakan ekspansi fiscal dan ekspansi moneter sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena terjadinya sinergi, di mana ekspansi fiscal yang berpotensi menigkatkan suku bunga dinetralisir dengan penurunan suku bunga melalui ekspansi moneter. Kombinasi kedua kebijakan tersebut lebih efektif dibandingkan apabila hanya dilakukan kebijakan ekspansi fiscal atau hanya dilakukan kebijakan ekspansi moneter. Secara komponen PDB, kombinasi kebijakan ekspansi fiscal dan moneter memberikan multiplier effect yang cukup besar sehingga mampu mendorong permintaan agregat dengan meningkatnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor serta impor. Secara sektoral, kombinasi kebijakan ekspansi fiskal dan moneter memberikan dampak positif berupa meningkatnya produksi di semua sector ekonomi. Hal ini karena didorong oleh adanya insentif fiskal (penurunan pajak, penurunan bea masuk impor, dan lainnya) sehingga sektor usaha meningkatkan investasi. Selain itu, adanya kenaikan permintaan agregat juga mendorong sektor usaha untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan tersebut. JEL Classification: D58, E12, E13, E52, E58, H25, H31, H53, H54 Keywords: Fiscal stimulus, monetary easing, financial computable general equilibrium, global financial crisis 194 I. Pendahuluan Krisis keuangan global telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun tajam. Krisis yang berasal dari permasalahan sub-prime mortgage di Amerika Serikat tersebut telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari sebesar 5.2% pada tahun 2007 menjadi sebesar 3.0% pada tahun 2008 dan bahkan pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0.9%. Dalam rangka mencegah memburuknya perekonomian akibat krisis tersebut, maka hampir semua Negara yang terkena imbas dari krisis melakukan countercyclical policies, berupa stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter. Dengan berbagai series kebijakan tersebut, pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan perekonomian domestik untuk mengkompensasi penurunan dari permintaan global. Stimulus fiskal yang dilakukan meliputi peningkatan pengeluaran pemerintah (government spending) dan penurunan pajak (tax cuts). Sementara pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penurunan suku bunga melainkan juga quantitative easing dengan membeli surat-surat berharga dalam memompa likuiditas di perekonomian. Dari sisi fiskal, fiskal defisit dibelahan ekonomi dunia menunjukkan kondisi yang semakin besar akibat tambahan stimulus fiskal, yaitu dari defisit fiskal sebesar -0.5% dari GDP pada tahun 2007 (pre-crisis) menjadi sebesar -6.7% pada tahun 2009. Sementara itu, Suku bunga bank sentral di dunia juga menurun tajam dan bahkan untuk beberapa negara suku bunga telah mendekati 0%. Di Amerika Serikat, the federal fund rate menurun tajam dari 5.25% pada September 2007 menjadi 0.25% pada December 2008. Tren penurunan suku bunga diikuti oleh hampir semua negara lain, yang rata-rata menurunkan suku bunga sebesar 330 basis poin (bps) pada negara maju dan rata-rata 300 bps di negara berkembang. (Battellino, 2009). Meskipun perdebatan masih berlangsung mengenai efektivitas kebijakan countercyclical tersebut, hampir semua negara masing-masing terus melanjutkan program stimulus fiskal dan penurunan suku bunga 195 dalam rangka menstimulasi ekonomi. Perdebatan mengenai efektivitas dari kebijakan itu terkait erat dengan berkembangnya keraguan akan kebijakan fiskal dan moneter countercyclical. Dari perspektif mainstream ekonomi khususnya sudut pandang klasik, stimulus fiskal dan kebijakan moneter bukan metode yang efektif untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi riil. Sementara itu, pandangan lain khususnya Keynes, berpendapat bahwa stimulus fiskal dan pelonggaran moneter dapat mencegah penurunan output riil. Peningkatan permintaan agregat, yang berasal dari stimulus fiskal dan pelonggaran moneter di tengah-tengah kekakuan harga dan kurangnya lapangan kerja, dapat berhasil meningkatkan output riil. Sebagaimana negara lainnya, Indonesia juga melakukan stimulus fiskal dan penurunan suku bunga dalam rangka mencegah perekonomian mengalami kontraksi akibat dari krisis keuangan global. defisit fiscal menunjukkan peningkatan sehubungan dengan peningkatan fiscal stimulus Rp73.3 triliun pada tahun 2009-walaupun realisasinya hanya dapat dicapai sebesar Rp32.9 triliun atau 44.9% dari anggaran. Sementara itu, suku bunga acuan, BI-rate, menurun tajam hingga mencapai 300 bps sehingga menjadi 6.5% pada April 2009. Untuk mengetahui efektivitas kedua kebijakan tersebut, paper ini akan mengkaji dampak dari kedua kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak dari kedua kebijakan tersebut adalah financial general equilibrium (FCGE). Selanjutnya, pada bagian dua akan dibahas mengenai teori dan implementasi dampak kebijakan fiskal dan moneter. Pada bagian tiga akan dibahas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi permasalahan krisis di Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dari kajian dan bagian akhir merupakan kesimpulan dari paper ini. II. Teori Peranan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam teori, terutama pada teori Keynesian, kebijakan fiskal dan moneter secara efektif mempengaruhi output riil. Kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu melalui stimulus fiskal, dapat meningkatkan permintaan 196 agregat melalui konsumsi domestik dan investasi. Dalam kondisi kekakuan harga, output jangka pendek riil akan meningkat. Di tengah permintaan global yang lemah akibat krisis keuangan global, stimulus fiskal dapat menningkatkan perekonomian domestik. Selanjutnya, peningkatan permintaan agregat dapat memberikan efek berlipat ganda dan meningkatkan pasokan agregat di sektor riil, khususnya jika ekonomi masih di bawah kapasitasnya (under-capacity), sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output dalam jangka pendek. Sementara itu, dari sudut pandang mikro perbankan, kebijakan moneter yang lebih longgar menggiring tren penurunan tingkat suku bunga, sehingga menurunkan biaya pendanaan (cost of fund) dan pada gilirannya memperkuat permintaan kredit, sehingga mendorong kegiatan konsumsi dan investasi. dan akhirnya permintaan agregat domestik. Dengan adanya kecenderungan kekakuan harga, maka penurunan suku bunga dapat meningkatkan output riil dalam jangka pendek. Selain itu, pembuat kebijakan juga mengadopsi kebijakan moneter yang diperlonggar selama krisis keuangan akibat likuiditas yang semakin menghilang di pasar uang. Kurangnya likuiditas tambahan di pasar keuangan menyebabkan kekurangan likuiditas di lembaga keuangan, yang mengikis kepercayaan publik terhadap bank. Hal ini dapat mempengaruhi pergerakan bank dan meningkatkan risiko sistemik dalam sistem perbankan secara keseluruhan, yang selanjutnya merusak pembiayaan pada dunia bisnis dan pada akhirnya merugikan perekonomian. Selain itu, kurangnya kepercayaan pada bank dapat mendorong masyarakat umum untuk melakukan diversifikasi ke aset nyata atau aset asing, sehingga memperburuk inflasi dan memulai aliran modal. Meskipun demikian, pandangan klasik menyatakan bahwa stimulus fiskal bersifat netral terhadap output riil. Pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah akan membentuk defisit anggaran, yang oleh karenanya, dalam jangka panjang pajak harus kembali dinaikkan untuk memangkas defisit. Akibatnya masyarakat umum akan mengurangi pengeluaran sebagai bentuk antisipasi pajak yang lebih tinggi di kemudian hari. Penurunan 197 dalam pengeluaran rumah tangga ini akan menghilangkan efek peningkatan pengeluaran pemerintah, sehingga tidak berpengaruh nyata pada output (Ricardian equivalence). Selain itu, kebijakan moneter tidak akan efektif mengontrol output riil. Bahkan meski terjadi peningkatan nilai nominal pada permintaan agregat domestik sebagai akibat kebijakan pelonggaran moneter melalui penurunan suku bunga atau peningkatan penawaran uang, harga akan cenderung meningkat. Dalam hal ini, peningkatan permintaan agregat nominal akan diimbangi dengan peningkatan harga , sehingga secara riil output tidak akan meningkat. Ada banyak studi empiris dilakukan untuk mengukur peran stimulus fiskal dan pelonggaran moneter dalam meningkatkan permintaan agregat dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Freedman et al. (2009) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif di seluruh dunia dikombinasikan dengan kebijakan moneter akomodatif dapat memiliki efek multiplier yang signifikan pada perekonomian dunia. Blanchard dan Perotti (2002) dan Romer dan Romer (2008) menemukan bahwa stimulus fiskal dari 1 persen dari PDB berdampak pada meningkatnya PDB sebesar hampir 1 persen poin pada saat kebijakan digulirkan dan sebanyak 2 sampai 3 persen dalam beberapa tahun kedepannya saat puncak efek terjadi. Perotti (2005) menemukan multiplier yang jauh lebih kecil untuk negara-negara Eropa. Baru-baru ini, Freedman, et al. (2009) menemukan baik pengeluaran pemerintah dan atau transfer yang ditargetkan akan memiliki efek multiplier yang cukup besar pada perekonomian. Skenario yang ideal adalah ketika stimulus fiskal bersifat global, didukung oleh akomodasi moneter, dan sektor keuangan yang mengalami tekanan, juga didukung oleh pemerintah. Studi lintas negara yang dilakukan oleh Christiansen (2008) menemukan multiplier fiskal yang kecil terhadap perekonomian dan dalam beberapa kasus ditemukan multiplier dengan tanda negatif. Studi yang dilakukan oleh Giavazzi dan Pagano (1990) dan disurvei oleh Hemming, Kell, dan Mahfouz (2002) juga menemukan bahwa ekspansi fiskal memiliki efek multiplier negatif bagi perekonomian. 198 Di sisi kebijakan moneter, terdapat pula beberapa studi tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan stimulus fiskal yang dapat segera meningkatkan kegiatan ekonomi, kebijakan moneter perlu waktu lebih lama untuk menunjukkan dampak pada ekonomi. Hal ini karena sasaran utama dari kebijakan moneter adalah untuk mempertahankan kesenjangan output dan inflasi yang stabil. Di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa utama, ditemukan bukti substansial terhadap efektivitas inovasi kebijakan moneter pada parameter ekonomi riil (lihat Miskhin (2002), Christiano et al. (1999), Rafiq dan Mallick (2008) dan Bernanke et al. (2005)). Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa kejutan melalui kebijakan moneter hanya mengakibatkan beberapa efek kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan kadang-kadang tidak konsisten dengan harapan teoritis, terutama bagi perekonomian dengan tingkat pendapatan menengah. Ganev et al. (2002) misalnya, mempelajari efek terhadap guncangan moneter di sepuluh negara Eropa Tengah dan Timur (Central and Eastern Europe/ CEE) negara dan tidak menemukan bukti bahwa perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi output. Ada tiga pertanyaan yang paling umum yang diidentifikasi dalam beberapa literatur, yaitu pertanyaan likuiditas, pertanyaan harga dan pertanyaan nilai tukar (Chuku, 2009). Pertanyaan likuiditas merupakan penemuan dimana peningkatan agregat moneter disertai dengan peningkatan (bukan penurunan) suku bunga. Sementara pertanyaan harga merupakan temuan dimana kontraksi dalam kebijakan moneter melalui inovasi positif dalam suku bunga tampaknya mengakibatkan peningkatan (bukan penurunan) harga. Namun, yang paling umum dalam perekonomian terbuka adalah pertanyaan nilai tukar, yang merupakan temuan dimana peningkatan suku bunga dikaitkan dengan depresiasi (bukan apresiasi) dari mata uang lokal. Perekonomian biasanya menjadi lebih baik ketika otoritas fiskal dan moneter mengkoordinasikan kebijakan mereka. Krisis lalu telah membuat jelas bahwa selain mencapai kesenjangan output yang stabil dan inflasi yang stabil, para pembuat kebijakan juga harus memperhatikan banyak target, 199 termasuk komposisi output, perilaku harga aset dan leverage dari agen-agen yang berbeda. Hal ini juga memperjelas bahwa terdapat instrumen yang lebih banyak, yaitu kombinasi kebijakan moneter tradisional dan kebijakan fiskal (Blanchard et al, 2010.). Koordinasi kebijakan dapat mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kemungkinan bagi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan utama. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mengurangi kesenjangan kelebihan/permintaan output dan untuk menutup kesenjangan investasi. Jika otoritas moneter dominan, maka kemungkinan kombinasinya adalah pengetatan fiskal dan sedikit pelonggaran kebijakan moneter. Pengetatan fiskal digunakan untuk mengelola kelebihan kesenjangan output (dan dengan demikian mengurangi tekanan inflasi), bahkan jika perlu berkorban dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Ekspansi moneter adalah untuk memastikan kualitas pertumbuhan yang baik yakni pertumbuhan yang didukung oleh investasi (swasta) yang kuat. Sebaliknya, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan output yang berlebihan. Di tengah pandangan yang saling bertentangan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang countercyclical, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia terus berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan salah satu pilihan dalam mengatasi krisis ekonomi akibat krisis, sebagaimana tercermin dari defisit fiskal yang sedang berkembang dan penurunan suku bunga di seluruh dunia. Paket stimulus fiskal yang diperkenalkan oleh pemerintah di banyak negara di seluruh dunia untuk mengatasi krisis, telah mengakibatkan meroketnya defisit fiskal global dari -0.5% dari PDB pada tahun 2007 menjadi -6.7% pada tahun 2009 (IMF, 2009). Peningkatan defisit terbesar terjadi di negara maju; menurun dari -1.2% selama periode pra-krisis (2007) menjadi -8.9% pada tahun 2009 (Tabel 1). Sementara itu, negara-negara berkembang dan negara-negara berpenghasilan rendah masing-masing mengalami defisit -4.0% dan -3.8% pada tahun 2009, yang sebelumnya masing-masing mengalami surplus sebesar 0.7% dan defisit sebesar -0.2% pada masa sebelum krisis. 200 Tabel 1. Neraca Fiskal (dalam persen GDP) 2007 (Pra–krisis) 2009 2010 2014 -0.5 -6.7 -5.6 -2.8 Ekonomi maju -1.2 -8.9 -8.1 -4.7 Ekonomi berkembang 0.7 -4.0 -2.8 -0.7 Ekonomi tertinggal -0.2 -3.8 -2.0 -1.4 -1.0 -7.9 -6.9 -3.7 G-20 ekonomi maju -1.9 -9.7 -8.7 -5.3 G-20 ekonomi berkembang 0.3 -5.1 -4.1 -1.3 Dunia Negara-negara G-20 Sumber: IMF Berdasarkan urutan negara, peningkatan terbesar dalam defisit fiskal terjadi di Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Perancis, dengan defisit masing-masing sebesar -12.5%, -11.6%, -10.5% dan -8.3% dari PDB pada tahun 2009, masing-masing dibandingkan dengan -2.8 %, -2.6%, -2.5% dan -2.7% pada tahun 2007. Sementara itu, defisit fiskal terbesar yang dilaporkan oleh negara ekonomi berkembang dialami oleh India dengan defisit mencapai -10.4% tahun 2009, dibandingkan dengan -4.4% di tahun 2007. Komposisi stimulus fiskal mencakup konsumsi publik dan transfer serta investasi, khususnya di bidang infrastruktur, pemotongan pajak pekerja, pemotongan pajak konsumsi, pemotongan pajak modal, dan pendapatan lainnya. Secara umum, sebagian besar stimulus fiskal diberikan dalam bentuk konsumsi masyarakat, transfer serta investasi. Selain stimulus fiskal, pemerintah beberapa negara juga memberikan dukungan kepada sektor keuangan dan sektor lainnya, termasuk pembiayaan dimuka. Pada Agustus 2009, jumlah rata-rata dukungan keuangan yang diberikan oleh 201 negara-negara anggota G-20 mencapai 2.2% dari PDB untuk injeksi modal ke sektor keuangan, 2.7% dari PDB untuk pembelian aset dan pemberian pinjaman melalui Departemen Keuangan, 8.8% untuk jaminan dan 3.7% untuk pembiayaan dimuka untuk pemerintah. Selain itu, dalam rangka mengurangi perlambatan ekonomi global, bank sentral di banyak negara mengambil tindakan agresif untuk melonggarkan posisi kebijakan moneter mereka. Beberapa negara menurunkan suku bunga mereka mendekati nol. Di Amerika Serikat, Federal Reserve memangkas Fed Fund Rate dari 5.25% menjadi 0.25% pada Desember 2008. Bank sentral lain, misalnya Australia, Inggris, Eropa dan Asia juga ikut mengurangi tingkat kebijakan mereka sebesar 0.4% hingga 5.25% dari pertengahan 2007 sampai awal 2009. Dukungan lebih lanjut untuk meredakan moneter, berasal dari kebijakan yang dirancang untuk memompa likuiditas ke pasar keuangan yang sangat memerlukannya, melalui pembelian aset serta pinjaman dana pemerintah, penyediaan likuiditas dan dukungan bank sentral yang masing-masing mencapai USD 1,436 miliar dan USD 2,804 miliar (IMF, 2009). Untuk menopang sektor perbankan, sejumlah pemerintah juga menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan jaminan simpanan maupun jaminan lainnya untuk berbagai pinjaman dan bantuan modal bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas, sebagai rangkaian upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Susunan kebijakan yang diambil berhasil menghilangkan risiko sistemik di pasar keuangan, mendorong optimisme dan mengembalikan kepercayaan pasar pada awal 2009. Likuiditas tambahan dari pelonggaran kuantitatif telah mengurangi ketatnya pasar uang dan intervensi yang dilakukan di negara maju serta pemulihan sistem keuangan, telah meredakan ancaman risiko sistemik dan memulihkan kepercayaan pelaku pasar keuangan. Pembelian surat berharga oleh bank sentral mampu mengurangi biaya pembiayaan dan mengembalikan pasar keuangan dari mati suri yang diakibatkan keengganan pasar untuk menyerapnya akibat risiko tinggi. Ekonomi global telah secara bertahap melakukan rebound di balik pemulihan sektor keuangan, yang meningkatkan likuiditas dalam per202 ekonomian. Didukung oleh stimulus fiskal yang signifikan, konsumsi rumah tangga juga meningkat, yang selanjutnya mendorong kegiatan industri pada awal 2009. Penurunan suku bunga yang agresif dan pembelian sekuritas berbasis hipotek menyebabkan suku bunga KPR menjadi lebih rendah dan karenanya mendorong pemulihan harga perumahan. Perbaikan kinerja sektor keuangan dan beberapa indikator sektor riil membantu memulihkan kepercayaan konsumen dan bisnis dalam pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Berdasarkan data dari World Economic Outlook edisi April 2010, pertumbuhan tahunan ekonomi dunia mencapai sekitar 3.25% selama kuartal kedua tahun 2009, kemudian menguat lebih dari 4.5% pada paruh kedua tahun ini. Alhasil, pertumbuhan ekonomi global hanya mengalami kontraksi sebesar -0.6% di tahun 2009, lebih baik dari proyeksi awal IMF sebesar -0.8% sebagaimana tercantum dalam edisi Januari WEO. Pemulihan ekonomi global ini, yang telah melebihi perkiraan awal, meningkatkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan kembali ke awal lintasan normal di tahun 2010. Keyakinan tersebut semakin ditopang oleh pertumbuhan luas dalam produksi dan perdagangan internasional selama semester kedua 2009. Di negara maju, siklus persediaan bisnis telah membalik dan konsumsi telah meningkat di Amerika Serikat. Di negara berkembang dan negara-negara dengan perkembangan pasar yang cepat (emerging market), sinyal positif pertumbuhan ekonomi global juga tercermin dari kuatnya permintaan domestik. Laju pemulihan ekonomi global bervariasi antar wilayah dan negara sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masing dan kebijakan yang ditempuh. Secara keseluruhan, negara-negara berkembang berekspansi sebesar 2.4% pada tahun 2009, dimana negara-negara Asia seperti Cina, India dan Indonesia memimpin dengan pertumbuhan yang kuat. Sementara itu, negara-negara maju mengalami kontraksi sebesar 3.2%. Meskipun demikian, dengan ekonomi global yang mulai mengalami akselerasi yang cepat pada semester kedua tahun 2009, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melebihi proyeksi IMF pada tahun 2010, mencapai 4.2%. 203 III. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia di Tengah Krisis Finansial Global Menghadapi krisis keuangan global, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiscal stimulus dan monetary policy easing untuk memerangi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiscal stimulus tersebut meliputi peningkatan expenditure dan tax cuts. Stimulus fiskal yang bersifat expenditure ditargetkan sebesar Rp 12,2 triliun yang terdiri dari pengeluaran untuk proyek infrastruktur dan non-infrastruktur. Proyek non-infrastruktur antara lain meliputi pelatihan keterampilan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), penambahan dana penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Selain itu Pemerintah juga melaksanakan stimulus yang bersifat penurunan revenue yaitu dengan cara mengurangi tingkat pajak maupun meningkatkan subsidi pajak dan non pajak yang ditanggung pemerintah. Stimulus ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat (rumah tangga ) dan insentif bagi dunia usaha (perusahaan) di tengah melemahnya perekonomian dunia. Untuk tahun 2009, diperkirakan penghematan yang diterima oleh Perusahaan dan Perorangan melalui penurunan tingkat PPh adalah sebesar Rp 50,3 triliun. Bila dibandingkan dengan data Penerimaan PPh 2008 yang sebesar Rp 305 triliun, maka diperoleh angka penurunan (shock) untuk PPh Perusahaan 9,3% dan PPh Perorangan 7,7%. Selain itu, stimulus fiskal juga dilakukan pemerintah melalui keringanan PPN untuk minyak goreng, bahan bakar nabati (BBN) dan kegiatan eksplorasi migas sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan nilai penerimaan PPN 2008 sebesar Ro 195,5 triliun, maka stimulus fiskal dari PPN ini adalah sebesar 1,79%. Terakhir adalah keringanan Bea Masuk (BM) untuk bahan baku dan bahan modal sebesar Rp 2,5 triliun yang berarti terjadi penurunan sebesar 14% dari tahun 2008 (pendapatan dari Bea Masuk Rp 17,8 triliun). Secara nominal, stimulus fiskal dari sisi pengurangan pajak adalah sebesar Rp 60,5 triliun yang akan berdampak pada ekonomi melalui mekanisme shock PPh, PPN dan BM. Secara ringkas, paket stimulus fiskal pada tahun 2009 di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. 204 Tabel 2. Stimulus Fiskal Indonesia untuk tahun 2009 Deskripsi A B C Tax-saving Payment Anggaran Pemerintah (Triliun Rupiah) % dari PDB Realisasi (Oktober 2009) % dari PDB % realisasi dari anggaran 43.0 0,82 20.5 0,39 47.8 1. Pengurangan tarif 13.5 pajak pendapatan perorangan (35% D 30%) dan kelebihannya 0,26 5.2 0,10 38.5 2. Meningkatkan batas minimum menjadi Rp15.8 million 11.0 0,21 2.5 0,05 23.1 3. Penurunan tingkat pajak pendapatan badan usaha (30% D 28%) dan perusahaan terdaftar D 5% lebih rendah 18.5 0,35 12.8 0,24 69.2 SUbsidi bea masuk /subsidi pajak untuk bisnis 13.3 0,25 3.8 0,07 28.4 1. PPN minyak goreng 0.8 0,02 1.5 0,03 182.4 2. PPN bio fuel 0.2 0,004 - 0,00 - 3. PPN eksplorasi migas 2.5 0,05 1.0 0,02 40.2 4. Pajak penerimaan untuk Geotermal 0.8 0,02 0.8 0,02 102.7 5. PPh 6.5 0,12 0.1 0,00 2.2 6. Bea masuk untuk bahan baku dan barang modal 2.5 0,05 0.3 0,01 13.6 Subsidi non pajak untuk bisnis dan kesempatan kerja 17.0 0,32 8.6 0,16 50.4 205 1. Penurunan harga BBM 2.8 diesel sebesar Rp.300/ liter 0,05 2.8 0,05 100.0 2. Potongan harga listrik untuk industri 1.4 0,03 1.0 0,02 75.0 3. Stimulus belanja untuk stimulus belanja 12.2 0,23 4.4 0,08 36.2 73.3 1.4 32.9 0.63 44.9 Total Stimulus dalam Rupiah Namun melihat perkembangannya, jumlah stimulus fiskal di atas diperkirakan tidak dapat terealisasi seluruhnya untuk tahun 2009. Sampai dengan Oktober 2009, stimulus fiskal yang telah terealisasi tercatat sebesar Rp 32.9 triliun atau sebesar 44,9% dari total rencana stimulus fiskal. Sosialisasi yang kurang baik, kehati-hatian dalam pengeluaran dan penetapan aturan yang lambat ditengarai menjadi penyebab rendahnya penyerapan stimulus fiskal. Selain stimulus fiskal, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga melakukan pelonggaran moneter secara signifikan dengan mengurangi policy rate-nya. Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan BI rate sebesar 300 bps dari 9.50% pada November 2008 menjadi 6.50% pada bulan Agustus 2009, kemudian mempertahankan rate pada posisi konstan sebesar 6.50% (Grafik 2). Laju pengurangan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pemotongan rate sebesar 50 bps setiap bulan dari Januari-Maret 2009 dan sebesar 25 bps selama April-Agustus 2009. Langkah-langkah tersebut diambil mengingat prospek inflasi yang rendah dan permintaan agregat yang lemah. Pelonggaran moneter, ditambah dengan stimulus fiskal, diharapkan bisa menjadi pendorong bagi kebijakan-kebijakan lain yang akan diambil untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik sambil terus menjaga stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan counter-cyclical, pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui negara lain di wilayah ini. Selanjutnya, kinerja seperti itu dimungkinkan 206 oleh kekuatan permintaan domestik, khususnya konsumsi, yang tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain dari kebijakan makro ekonomi, kemampuan ekonomi Indonesia untuk bertahan dari guncangan global ini terkait dengan karakteristik dari bank dan lembaga keuangan domestik yang masih cenderung konvensional dan memiliki tingkat exposure yang relatif rendah di bank-bank luar negeri, sehingga dapat meminimalkan dampak langsung dari gejolak pasar keuangan global. Hal lain yang mempengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia adalah karena Indonesia telah memperbaiki sistem perbankan yang sebelumnya telah diperkuat dan dikonsolidasi setelah krisis keuangan tahun 1998. Indikator makroekonomi terbaru menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh, efektif dalam mengimbangi perlambatan ekonomi Indonesia sebagai akibat dari krisis keuangan global. Di tengah melemahnya ekonomi global, perekonomian Indonesia telah berhasil mencatat kinerja yang cukup menjanjikan, dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 tercatat sebesar 6.1%. Namun, di menjelang akhir tahun 2008, perekonomian Indonesia mulai terpengaruh oleh dampak perlambatan ekonomi global. Hal ini terbukti dalam pertumbuhan hanya 5.2% pada kuartal keempat tahun 2008, di bawah triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5.9%. Namun, perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang signifikan sejak semester kedua tahun 2009. Terlepas dari fakta bahwa krisis ini telah menyebabkan banyak negara yang mengalami pertumbuhan negatif, Indonesia masih mampu bertahan tumbuh positif sebesar 4.5% di tahun 2009. 207 Grafik 1. Pertumbuhan PDB Indonesia Grafik 2. Perkembangan BI-Rate (Policy Rate) Nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh perkembangan krisis keuangan global. Pergerakan kurs relatif stabil sampai pertengahan September 2008. Namun, dampak penyebaran krisis keuangan global telah mendorong 208 investor melepas aset pada skala yang signifikan, sehingga memberi tekanan berat pada nilai tukar Rupiah pada triwulan IV tahun 2008. Selama tahun 2008, nilai tukar Rupiah dihadapkan pada volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tren penyusutan. Ratarata sepanjang tahun, rupiah melemah 5.4% dari Rp 9.140 per dolar AS pada tahun 2007 menjadi Rp 9.666 per dolar AS pada tahun 2008. Pada akhir tahun, Rupiah diperdagangkan pada Rp 10.900 per dolar AS, setelah kehilangan 13.8% (point to point) dari penutupan akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 9,393 per dolar AS. Selain itu terjadi pula peningkatan tajam dalam volatilitas dari 1.44% pada tahun 2007 menjadi 4.67% pada tahun 2008. Kondisi ketidakpastian di pasar uang asing sebagai dampak dari krisis yang sedang berlangsung di awal tahun 2009 memberikan tekanan berat kepada Rupiah pada triwulan pertama 2009. Nilai tukar Rupiah telah mencapai titik terendah pada level Rp 12.020 per dolar AS pada bulan Maret, awal tahun 2009, disertai dengan peningkatan volatilitas. Nilai tukar rupiah mulai mengalami tren apresiasi sejak triwulan kedua 2009. Kondisi ini didukung oleh kesinambungan dari beberapa faktor fundamental dalam negeri yang telah memulihkan persepsi investor global tentang pasar yang kembali aktif. Akibatnya, investor mulai kembali mau mengambil resiko untuk aset pasar keuangan domestik sehingga kemudian modal kembali mengalir ke pasar keuangan Indonesia. Selain itu, surplus transaksi berjalan masih tumbuh untuk mendukung rupiah untuk memperkuat tren ini. Perkembangan ini mengakibatkan apresiasi Rupiah sekitar 18.4% antara akhir Maret sampai dengan Desember 2009 dan ditutup pada level Rp. 9,425 per US Dollar (Grafik 3). Penguatan rupiah itu juga disertai dengan peningkatan volume perdagangan di pasar valuta asing. Secara keseluruhan, tingkat rupiah pada akhir tahun 2009 menguat 15.7% dibandingkan dengan tingkat pada akhir tahun 2008. Meskipun mengalami tren apresiasi, Rupiah masih mampu mendukung daya saing produk ekspor Indonesia. 209 Grafik 3. Nilai tukar Rupiah: level and volatilitas Grafik 4. CPI dan Inflasi Inti Tekanan inflasi bertahan cukup tinggi selama awal krisis. Inflasi CPI naik tajam di tahun 2008 menjadi 11.06% dari tingkat tahun sebelumnya 210 yang tercatat sebesar 6.59% (Grafik 4). Tekanan inflasi itu dipicu oleh lonjakan harga komoditas global, terutama oleh komoditas minyak dan makanan. Harga minyak yang tinggi tidak hanya mendorong inflasi impor, tetapi juga membawa inflasi harga yang lebih tinggi menyusul keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Peristiwa ini dikombinasikan dengan masalah dalam distribusi dan pasokan komoditas utama yang mendorong peingkatan ekspektasi inflasi yang juga memberikan tekanan ke atas pada inflasi inti di tahun 2008. Namun demikian, tekanan inflasi menurun cukup signifikan pada triwulan IV tahun 2008 seiring dengan harga komoditas global yang jatuh dan perlambatan perekonomian dunia yang semakin dalam. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dalam negeri pada Desember 2008 seiring dengan penurunan harga minyak dunia yang mengikuti tekanan inflasi. Jaminan pasokan beras dalam negeri merupakan faktor tambahan yang membantu menjaga kenaikan pada harga beras yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbagai kondisi ekonomi global, respon kebijakan yang diambil, dan faktor lainnya dalam ekonomi domestik memberikan kontribusi terhadap penurunan tekanan inflasi pada tahun 2009, dimana laju inflasi menurun tajam menjadi 2.78%. Berkebalikan dengan perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran menunjukkan perbaikan seiring dengan kondisi ekonomi yang terus membaik sejak semester kedua tahun 2009. Dibawah kondisi tersebut, pengangguran terbuka pada tahun 2009 sedikit menurun dari 8.1% pada Februari 2009 menjadi 7.9% pada bulan Agustus 2009. Namun, pengangguran setengah terbuka sedikit meningkat dari 31.1% pada bulan Agustus 2008 menjadi 31.6% pada bulan Agustus 2009. Penurunan pengangguran diperkirakan karena sebagian diserap oleh sektor informal, sebagaimana tercermin pada meningkatnya penggunaan tenaga kerja di sektor informal pada bulan Agustus 2009, yang mencakup 72.7 juta orang dibandingkan dengan 71.4 juta orang pada bulan Agustus 2008. Penurunan jumlah pengangguran dan perkembangan dari harga yang relatif stabil memberikan kontribusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan 211 di tahun 2009, yang menurun sekitar 14.15% dari total populasi (32.53 juta orang), dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang mencapai 15.42% dari total penduduk (34.96 juta orang). Penurunan paling tajam dari pengangguran terjadi terutama di daerah pedesaan sebesar 1.57 juta orang, sedangkan di daerah perkotaan hanya menurun sebanyak 0.86 juta orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan adalah peningkatan pendapatan riil harian petani, penurunan harga ratarata nasional beras dan inflasi stabil. Selain itu, penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan daya beli sebagai dampak dari distribusi bantuan langsung tunai (BLT), kenaikan upah minimum provinsi (UMP), penurunan harga bahan bakar, dan musim panen yang terjadi pada Maret 2009. Table 3. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Populasi Miskin Persentasi Populasi Area/ Tahun (juta) Miskin Urban 2006 14.49 13.47 2007 13.56 12.52 2008 12.77 11.65 2009 11.91 10.72 Rural 2006 24.81 21.81 2007 23.61 20.37 2008 22.19 18.93 2009 20.62 17.53 Urban + Rural 2006 39.30 17.75 2007 37.17 16.58 2008 34.96 15.42 2009 32.53 14.15 Sumber: BPS 212 IV. Dampak Stimulus Fiskal dan Pelonggaran kebijakan Moneter Untuk melihat dampak stimulus fiscal dan pelonggaran kebijakan moneter terhadap perekonomian digunakan model Financial Computable General Equilibrium (FCGE)4 yang didasarkan pada data Financial Social Accounting Matrix (FSAM) Indonesia tahun 2005. Sejumlah simulasi diujicobakan dengan menggunakan kondisi ekonomi pada akhir 2008 sebagai acuan (baseline) yakni ketika BI rate berada pada tingkat 9.25%. Tiga skenario kebijakan disimulasikan dan kemudian dibandingkan dengan baseline, yang akan menentukan efektivitas setiap kebijakan serta dua kebijakan tersebut digabung sebagai berikut: i. Skenario pertama memperhitungkan ekspansi fiskal tanpa ekspansi moneter. Ekspansi fiskal termasuk pengurangan pajak perusahaan, pengurangan pajak 9.3% di perusahaan tidak langsung (pajak penghasilan) dan pajak rumah tangga sebesar 7.7%, penurunan pajak langsung untuk komoditas pertambangan sebesar 1.79% dan penetapan bea masuk yang lebih rendah untuk bahan baku dan modal sebesar 14 %. Skenario ini mengakomodasi perkiraan dari realisasi stimulus fiskal sebesar 50% dari anggaran awal, dengan asumsi bahwa pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan anggaran stimulus sampai dengan akhir tahun 2009 (per Oktober 2009, total realisasi 44.9%). ii. Skenario kedua memperhitungkan kebijakan moneter tanpa dukungan kebijakan fiskal. Berdasarkan skenario ini tingkat suku bunga dipotong sebesar 2.75% sesuai dengan BI rate, yang berkurang dari 9.25% pada Desember 2008 menjadi 6.50% pada bulan Desember 2009 sejalan dengan inflasi yang rendah dan terkendali iii. Skenario ketiga mengasumsikan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dilaksanakan sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif. 4 Lihat lebih rinci model FCGE ini di Simorangkir dan Adamanti (2010) di Proceedings of the Ecomod2010, Istanbul, Turkey, July 2010 dan Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 13, No. 2, Oktober 2010. 213 Hasil simulasi mengenai dampak dari tiga skenario kebijakan pada variabel makroekonomi dan inflasi, neraca pemerintah, sektor dan insitusi produksi adalah sebagai berikut: a. Dampak Simulasi Kebijakan terhadap Variabel Ekonomi Makro dan Inflasi Hasil simulasi mengenai dampak dari tiga skenario terhadap variabel makroekonomi dan inflasi disajikan pada Tabel 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter ekspansif lebih efektif dalam hal peningkatan PDB. Kebijakan gabungan meningkatkan GDP 1.057% dibandingkan dengan 0.996% untuk hanya kebijakan fiskal dan 0.061% untuk kebijakan moneter sendiri, mengingat potensi kenaikan suku bunga karena kebijakan fiskal akan diperhitungkan oleh potensi penurunan suku bunga karena kebijakan moneter. Dalam hal komponen PDB, kebijakan fiskal ekspansif memberikan efek pengganda yang besar yang mendorong investasi, konsumsi dan impor/ekspor. Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan permintaan agregat dan PDB. Sementara itu, kombinasi dari kebijakan fiskal dan moneter ekspansif tidak memperburuk tekanan inflasi (-0.076%) dibandingkan dengan kebijakan moneter semata-mata, yang cenderung mendorong inflasi (0.097%). Inflasi bisa dikendalikan melalui bea impor yang lebih rendah yang mengurangi biaya produksi untuk industri pengolahan bahan baku impor dan PPN yang dipotong untuk barang-barang strategis (minyak goreng, biofuel). 214 Tabel 4. Simulasi dari dampak kebijakan pada variabel makro dan inflasi Skenario (% perubahan) Kombinasi Makro Variabel Kebijakan Kebijakan MonKebijakan Fiskal eter Fiskal & Moneter PDB 0.996 0.061 1.057 Konsumsi 1.291 0.069 1.360 Investasi 0.951 0.049 0.999 Pengeluaran Pemerintah 0.740 0.080 0.819 Ekspor 2.220 0.050 2.270 Impor 2.904 0.061 2.966 ,QÀDVL -0.173 0.097 -0.076 Mekanisme penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk variabel makroekonomi disajikan pada Gambar 2. Kebijakan fiskal ekspansif dalam bentuk pengurangan pajak memberdayakan pelaku bisnis dan rumah tangga dengan dana lebih, yang mendukung daya beli dan meningkatkan konsumsi sebesar 1,36% (di bawah skenario kebijakan gabungan). Lebih jauh lagi, peningkatan konsumsi memperkuat permintaan agregat, yang mendorong produksi lebih besar. Ini sejalan dengan biaya produksi yang lebih rendah pasca pengurangan pajak penghasilan badan usaha dan PPN serta tingkat suku bunga yang relatif rendah yang mendorong investasi. Produksi juga meningkat di balik gelombang impor (mayoritas bahan baku sektor produksi adalah impor) yang meningkat sebesar 2.966% sebagai akibat dari bea masuk yang lebih rendah (BM). Lebih lanjut, produksi didorong oleh pertumbuhan di sektor ekspor sebesar 2.270%. Sementara itu, kebijakan fiskal ekspansif telah mendorong pengeluaran melalui anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur dan non-infrastruktur yang mendorong kegiatan investasi, yang tumbuh 215 sebesar 0.999%. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga mendorong permintaan agregat yang mendorong peningkatan PDB. Bersama dengan ekspansi kebijakan fiskal, tren penurunan BI rate yang merupakan kebijakan moneter ekspansif telah memperbaiki iklim investasi dan oleh karenanya meningkatkan permintaan agregat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Penurunan BI rate mengimbangi kenaikan suku bunga akibat ekspansi kebijakan fiskal, maka dua kebijakan ini menciptakan sinergi yang kuat dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, pengaruh kolektif dari peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor telah meningkatkan GDP sebesar 1,057%. Gambar 2. Mekanisme Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter b. Hasil Simulasi dari Dampak Kebijakan pada Neraca Pemerintah Kebijakan fiskal ekspansif merupakan beban bagi APBN karena kenaikan defisit keuangan sebagai akibat dari penurunan pendapatan pajak (pajak penghasilan, PPN, Bea Masuk) dan peningkatan belanja pemerintah, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5 . 216 Tabel 5. Simulasi dari Dampak Kebijakan pada Neraca Pemerintah Skenario (% changes) Neraca Pemerintah Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kombinasi Kebijakan Fiskal & Moneter Pendapatan -6.43 0.19 -6.25 Pengeluaran 1.18 0.15 1.33 'H¿VLW -1.59 0.01 -1.58 Tabel 5 menunjukkan bahwa dampak dari kombinasi kebijakan fiskal dan moneter menyebabkan kenaikan yang relatif kecil pada defisit fiskal (-1.58%) dibandingkan dengan respon murni fiskal (-1.59%). Namun, defisit fiskal tetap dalam batas maksimum sebesar -3% untuk menjaga kesinambungan fiskal. Dalam hal pendapatan pemerintah, kombinasi kebijakan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan yang lebih kecil (-6.25%) dibandingkan dengan hanya respon fiskal semata(-6.43). Dalam hal belanja pemerintah, koordinasi kebijakan ini menyebabkan total belanja yang yang lebih besar (1.33%) dibandingkan dengan kebijakan fiskal semata (1.18%). Sebaliknya, kebijakan moneter ekspansif melalui suku bunga yang lebih rendah memiliki dampak fiskal netral (0.01%). c. Dampak Simulasi Kebijakan terhadap Sektor Simulasi yang menggunakan gabungan kebijakan fiskal dan moneter telah dijalankan untuk menggambarkan dampak kebijakan oleh sektor ekonomi seperti disajikan dalam Tabel 6. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, meningkatkan produksi semua sektor ekonomi. Hal ini sebagian besar didorong oleh insentif fiskal yang mendorong sektor usaha untuk meningkatkan investasi. Selain itu, permintaan agregat yang lebih kuat dari peningkatan konsumsi dan belanja pemerintah juga mendorong sektor usaha untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. 217 Tabel 6. Simulasi dari Dampak Kebijakan pada Sektor Produksi Sektor % perubahan Produksi Ekspor Impor Pertanian 1.59 3.23 0.79 Pertambangan 0.35 -0.18 1.40 Manufaktur (Minyak) 0.11 -0.64 1.07 Manufaktur (Non minyak) 1.93 3.66 4.37 Listrik, gas & air 0.97 0.00 0.00 Konstruksi 0.67 0.00 0.00 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.61 3.17 0.85 Transportasi & Komunikasi 1.19 1.71 0.88 Keuangan 0.97 0.92 1.00 Jasa Lain 1.21 3.14 0.21 Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam produksi meliputi non-migas, perdagangan, pertanian, jasa serta komunikasi dan transportasi dengan kisaran masing-masing 1.93%, 1.61%, 1.59%, 1.21 dan 1.19%. Impor melonjak sebagai akibat dari peningkatan produksi karena masih banyak bahan baku yang diimpor. Peningkatan impor juga didorong oleh harga yang lebih murah karena pengurangan bea masuk. Sektor yang tercatat mengalami kenaikan impor terbesar meliputi industri pertambangan, non-migas dan migas dengan kisaran masing-masing 4.37%, 1.40% dan 1.07%. Dengan mengacu pada ekspor, dampak ekspansi kebijakan fiskal dan moneter yang menstimulasi kegiatan produksi, juga meningkatkan volume ekspor dari semua sektor. Sektor nonmigas, pertanian, perdagangan dan jasa mengalami kenaikan ekspor masingmasing sebesar 3.66%, 3.23%, 3.17% dan 3.14%. 218 d. Dampak Simulasi Kebijakan terhadap Institusi dan Rumah Tangga Tujuan utama kebijakan yang terkait oleh Pemerintah dan Otoritas Moneter adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, maka perlu untuk menguji dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perubahan pendapatan dan konsumsi institusi terutama rumah tangga, seperti disajikan pada Tabel 7. Table 7. Perubahan pada Pendapatan dan Konsumsi Institusi Institusi % perubahan Pendapatan Pajak Konsumsi 4.05 2.87 2.53 -4.39 2.63 Perusahaan Rumah Tangga Rural Miskin Rumah Tangga Rural Tidak Miskin 2.19 -4.70 1.79 Rumah Tangga Urban Miskin 1.42 -5.42 1.68 Rumah Tangga Urban Tidak Miskin 1.60 -5.26 0.87 Ada empat kategori rumah tangga, yaitu rural miskin dan rural tidak miskin, serta urban miskin dan urban tidak miskin. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter ekspansif meningkatkan pendapatan dari seluruh rumah tangga dengan kadar bervariasi dengan kenaikan tertinggi terjadi pada pendapatan rumah tangga rural miskin dan rural tidak miskin sebesar masing-masing 2.53% dan 2.19%. Peningkatan pendapatan institusi sebagian dikarenakan keringanan pajak oleh pemerintah maupun karena subsidi dari pemerintah untuk peningkatan daya beli rumah tangga. Rumah tangga urban miskin dan urban tidak miskin mengalami penurunan pajak terbesar sebesar 5.42% dan 5.26% masing-masing. Sebaliknya, perusahaan sebenarnya membayar pajak lebih banyak, yang tampaknya sejalan dengan peningkatan yang signifikan dalam produksi. 219 Daya beli rumah tangga meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan dan inflasi yang relatif terkendali. Lebih jauh lagi, peningkatan pendapatan mendorong konsumsi rumah tangga. Rumah tangga rural miskin dan rural tidak miskin mengalami kenaikan konsumsi tertinggi sebesar masing-masing 2.63% dan 1.79%. V. Kesimpulan Selama krisis keuangan global, kombinasi pelonggaran fiskal dan moneter ekspansif secara signifikan telah meringankan krisis ekonomi. Sebagai hasil dari sinergi kebijakan, potensi kenaikan suku bunga karena kebijakan fiskal ekspansif dapat diimbangi oleh kebijakan moneter yang meredakan tekanan inflasi. Kebijakan gabungan lebih efektif daripada kebijakan yang diambil sendiri-sendiri. Dari sisi PDB, kebijakan fiskal dan moneter gabungan memberikan efek pengganda yang signifikan untuk mendorong permintaan agregat melalui peningkatan konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan ekspor/impor. Terhadap sektor, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif meningkatkan produksi di semua sektor ekonomi melalui insentif fiskal (pemotongan pajak, bea masuk rendah dan lain-lain) yang mendorong sektor usaha untuk meningkatkan investasi. Selain itu, permintaan agregat kuat juga mendorong sektor usaha untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi permintaan tersebut. Dari sisi institusi, pajak yang lebih rendah dan peningkatan subsidi mengangkat pendapatan rumah tangga dan juga daya beli rumah tangga. Lebih lanjut, pendapatan yang lebih tinggi ini mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih besar. Dalam hal anggaran pemerintah, kombinasi ekspansi kebijakan fiskal dan moneter menambah defisit fiskal akibat penurunan pendapatan dari pajak (pajak penghasilan, PPN, bea impor) dan pengeluaran pemerintah lebih. Namun, defisit fiskal masih berada di bawah ambang batas maksimum -3%. 220 REFERENSI Bank Indonesia, 2010, “Laporan Perekonomian Indonesia 2009: Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional”, Bank Indonesia Bank Indonesia, 2009a, “2008 Economic Report on Indonesia.” Bank Indonesia, 2009b, “Indonesian Economic Outlook 2009-2014: Global Financial Crisis and Its Impact on Indonesian Economy” Bernanke, Ben, Jean Boivin and Piotr Eliasz (2005), “Measuring the effects of monetary policy: A Factor-Augumented vector autoregressive approach”, Quarterly Journal of Economics (2) 387-422 Taylor (Eds), The Handbook of Macroeconomics Vol. 1 North-Holland, Amsterdam, pp. 65-148. Blanchard, O., and R. Perotti, 2002, “An Empirical Characterization of Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”, Quaterly Journal of Economics, Vol. 117, pp. 1329-168. Blanchard, Oliver, Giovanni Dell’Ariccia and Paolo Mauro, 2010, “Rethinking Macroeconomic Policy”, IMF Staff Position Note Christiansen, L., 2008, “Fiscal Multipliers-A Review of the Literature”, Appendix II to “IMF Staff Position Note 08/01, Fiscal Policy for the Crisis” (Washington: International Monetery Fund). Christiano, Lawrence, Martin Eichenbaum, and Charles Evans (1999), “Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? In Woodford, Michael and John Taylor (Eds)”, The Handbook of Macroeconomics Vol. 1 North-Holland, Amsterdam, pp. 65-148. Chuku, Chuku A., 2009, “Measuring the Effects of Monetary Policy Innovations in Nigeria: A Structural Vector Autoregressive (SVAR) Approach”, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research Vol. 5 No. 5 2009 221 Freedman, C., M. Kumhof, D. Laxton, and J. Lee, 2009, “The Case for Global Fiscal Stimulus”, IMF Staff Position Note 09/03 (Washington: International Monetary Fund). Freedman, Charles, et.al., 2009, “The Case for Global Fiscal Stimulus”, IMF Staff Position Note Giavazzi, F. And M. Pagano, 1990, “Can Severe Fiscal contractions be Expansionary? Tales of Two Small European Countries”, NBER Macroeconomics Annual 1990 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau on Economic Research), pp. 75-122. Hemming, R., M. Kell, and S. Mahfouz, 2002, “The Effectiveness of Fiscal Policy in Strimulating Economic Activity – A Review of the Literature”, IMF Working Paper 02/208 (Washington: International Monetary Fund). International Monetary Fund, 2009, ”World Economic Outlook April 2009: Crisis and Recovery” (Washington DC: IMF) International Monetary Fund, 2009, ”World Economic Outlook October 2009: Sustaining the Recovery” (Washington DC: IMF) International Monetary Fund, 2009, ”World Economic Outlook April 2009: Rebalancing Growth” (Washington DC: IMF) Mishkin, Frederick (2002), “The role of output stabilization in the conduct of monetary policy”, Working Paper No. 9291. NBER. Perotti, R., 2005, “Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries”, CEPR Discussion Paper No. 4842 (London: Centre for Economic Policy Research). Rafiq, M.S. and S.K. Mallick (2008), “The effect of monetary policy on output in EMU3: A sign restriction approach”, Journal of Macroeconomics (30) 1756-1791. Romer, C., and D. Romer, 2008, “The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates based on a New Measure of Fiscal Shocks” (Unpublised Manuscript: University of California at Berkeley). 222 Simorangkir, Iskandar, Haris Munandar, 2009, “Understanding the Roles of Fiscal Stimulus in Maintaining Resilience of Indonesian Economy: A Computable General Equilibrium Approach”, Institute of Southeast Asian Studies Simorangkir, Iskandar dan Justina Adamanti, 2010. “Peran Stimulus Fiskal dan Pelonggaran Kebijakan Moneter Pada Perekonomian Indonesia Selama Krisis Finansial Global: Dengan Pendekatan Financial Computable General Equilibrium”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 13, No. 2, Oktober 2010 Staff of the Fiscal Affairs Department, IMF, 2009, “The State of Public Finances Cross – Country Fiscal Monitor: November 2009”, IMF Staff Position Note Tjahjono, Endy D., M. B. Bathaluddin, Justina Adamanti, 2009, “SEMAR 2009: Suatu Model Financial Computable General Equilibrium”, Bank Indonesia Working Paper No. WP/20/2009 223 224 INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI INDONESIA Dr. Wijoyo Santoso, SE. MA.1 I. Latar Belakang Masalah Sebagian besar bauran kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia periode 1984-2010 adalah kebijakan moneter ketat-fiskal ketat (komplemen) dan kebijakan moneter ketat-fiskal longgar (substitusi) seperti pada grafik 1.1.2 Kebijakan moneter ketat dicerminkan oleh meningkatkan suku bunga rill SBI 1 bulan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya kebijakan moneter longgar. Kebijakan fiskal longgar diartikan sebagai meningkatkan rasio keseimbangan fiskal terhadap PDB dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya dengan kebijakan fiskal ketat. 1 2 Peneliti Utama Senior PPSK-Bank Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 2011. Pengukuran arah kebijakan moneter dan fiskal mengacu pada Mohanty dan Scatigma (2003). Arah kebijakan moneter ketat diukur dengan perubahan suku bunga riil (SBI): jika perubahan suku bunga riil positif berarti arah kebijakan moneter cenderung ketat dan sebaliknya. Arah kebijakan fiskal diukur dengan perubahan rasio keseimbangan fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika perubahan rasio positif berarti arah kebijakan fiskal ketat dan sebaliknya. 225 Dari 27 observasi selama periode 1984-10 terdapat 16 interaksi kebijakan moneter dan fiskal bersifat komplemen sedangkan yang bersifat subtitusi sebanyak 11 observasi. Interaksi kebijakan moneter fiskal yang bersifat komplemen hampir seimbang antara kebijakan moneter ketatfiskal ketat dengan kebijakan moneter longgar-fiskal longgar sedangkan kebijakan yang bersifat substitusi lebih didominasi oleh kebijakan moneter longgar-fiskal ketat. Selama periode pengamatan (27 tahun) akumulasi perubahan suku bunga riil SBI 1 bulan masih positif sebesar 3,95% sedangkan akumulasi perubahan keseimbangan fiskal masih positif 1,56% dari PDB. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal seperti grafik 1.1 di atas diduga belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selama periode observasi (1984-10) inflasi rata-rata per tahun mencapai 10,57 persen, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 5,04 persen dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 5,6 persen dari jumlah angkatan kerja. 226 Apakah bauran kebijakan seperti terebut di atas sudah yang terbaik bagi bangsa Indonesia? Kombinasi arah perubahan kebijakan moneter yang hampir selalu cenderung ketat dengan arah perubahan kebijakan fiskal yang seimbang antara ketat dan longgar diduga belum memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa kebijakan moneter dan fiskal sebaiknya berkoordinasai dalam rangka stabilisasi harga dan output. Pertama, terbatasnya ketersediaan instrumen untuk mencapai target. Blinder (1982) mengungkapkan keterbatasan instrumen tersebut dapat bersumber dari pertimbangan waktu dampak instrumen terhadap target yang dapat dibedakan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan durasi waktu ini dan adanya unsur ketidakpastian mengenai efektivitas instrumen tersebut menjadi alasan kuat mengapa kebijakan fiskal dan moneter harus berkoordinasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, agar menghasilkan dampak optimal terhadap pencapaian target. Kedua adalah untuk menjaga stabilisasi ouput dan inflasi agar tidak memburuk sebagai akibat kurangnya koordinasi antara kebijakan 227 moneter dan fiskal. Adanya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat memberikan pemisahan yang tegas dari dua kebijakan tersebut atas dasar struktur tenggang waktu kebijakan. Abel (2002) menyarankan agar kebijakan moneter digunakan untuk melakukan stabilisasi ekonomi dalam jangka pendek sedangkan kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai target perekonomian jangka menengah dan panjang. Sementara itu, kebijakan moneter dalam jangka panjang dapat difokuskan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil. Taylor (2000) menambahkan bahwa jika kebijakan fiskal difokuskan ke arah target jangka menengah, kebijakan moneter seharusnya memberikan bobot yang lebih besar kepada stabilisasi output3. Alasan ketiga pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal adalah adanya perbedaan pendapat atau persepsi antara dua otoritas tersebut mengenai apa yang terbaik bagi suatu bangsa. Binder (1982) menyebutkan tiga faktor yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi fiskal dan moneter sebagai berikut: (a) otoritas fiskal dan otoritas moneter memiliki tujuan yang berbeda terhadap apa yang sebenarnya terbaik bagi masyarakat, (b) dua otoritas tersebut dapat memiliki pendapat yang berbeda mengenai dampak dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap perekonomian dan mungkin mereka menganut dasar teori ekonomi yang berbeda, dan (c) kemungkinan dua otoritas tersebut memiliki proyeksi perekonomian yang berbeda. Pentingnya interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia sudah disadari sejak dibentuknya Dewan Moneter menurut UU No. 11 tahun 1953 yang bertujuan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan tingkat inflasi yang dapat diterima. Sejak berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia tugas pokok Bank Indonesia mengalami perubahan mendasar dari sasaran ganda ke sasaran tunggal. Selain itu, status Bank Indonesia berubah 3 Hal sebaliknya diungkapkan oleh Stevenson (2002) bahwa bank sentral seharusnya tidak berperan aktif dalam stabilisasi ouput namun berperan secara tidak langsung dalam stabilisasi output melalui pengendalian inflasi yang rendah. Negara yang menerapkan kerangka target inflasi akan memberikan bobot lebih besar pada pengendalian ekspektasi inflasi sehingga melalui kebijakan moneter yang kredible dapat memperkecil volatilitas tingkat inflasi dan ouput. 228 menjadi lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sejak independen, Bank Indonesia tidak lagi dibantu Dewan Moneter dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Interaksi hubungan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah sejak berlakunya undang-undang ini semakin menjauh. Pihak lain, termasuk pemerintah, dilarang melakukan segala campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Setelah Dewan Moneter dibubarkan, koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk rapat dan forum khususnya dalam hal saling tukar-menukar informasi antara otoritas moneter dan fiskal dalam rapat kabinet pemerintah, rapat dewan gubernur di Bank Indonesia, Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK), dan Tim Pengendalian Inflasi. II. Tinjauan Pustaka Jumlah penelitian interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia masih relatif terbatas. Adam dan Billi (2005) menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal dengan bias pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter dengan bias inflasi akan menyebabkan kerugian sosial yang sangat berarti. Javet dan Sahinoz (2005) menyatakan bahwa target keseimbangan internal dan eksternal dapat dicapai dengan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan fiskal dan moneter. Simorangkir (2005) menyatakan kordinasi kebijakan moneter dan fiskal memberikan kerugian sosial yang lebih kecil dibandingkan tanpa koordinasi. Kebijakan moneter hendaknya memperhatikan pertumbuhan ekonomi mengingat besarnya kerugian sosial yang diderita perekonomian nasional jika bank sentral hanya memperhatikan inflasi. Muscatelli dkk. (2004) menyimpulkan bahwa interaksi kebijakan moneter dan fiskal akan bergerak searah atau berlawan sangat dipengaruhi oleh sifat goncangan yang terjadi. Selanjutnya, respon kebijakan moneter yang optimal akan dipengaruhi oleh beberapa skenario goncangan pada kebijakan fiskal dan dampak interaksi kebijakan moneter dan fiskal terhadap kesejahteraan sosial akan positif apabila kebijakan fiskal bersifat eksogen. 229 Leitimo (2004) menekankan jika terjadi konflik mengenai besarnya kesenjangan output, kebijakan moneter dan fiskal akan menghasilkan volatilitas suku bunga dan nilai tukar yang signifikan sebagai akibat konflik kesenjangan output. Maryatmo (2004) menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara variabel fiskal dan variabel moneter dan hubungan timbal balik antara instrumen fiskal dan moneter saling menghilangkan (substitusi). Mochtar (2004) menyatakan bahwa dalam menjaga stabilisasi harga, otoritas moneter memerlukan komitmen yang tinggi dari otoritas fiskal terhadap disiplin dan kesinambungan fiskal. Dixit dan Lambertini (2003) menyimpulkan jika otoritas fiskal dan moneter bersepakat mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang akan dicapai, hasil ideal dapat dicapai secara independen tanpa harus mempersoalkan bobot pertumbuhan ekonomi atau inflasi, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, komitmen moneter dan siapa yang ‘bergerak’ duluan antara kebijakan moneter dan fiskal. Bennet (2002) menyarankan untuk mengurangi bias antara kebijakan fiskal dan moneter diperlukan koordinasi kebijakan baik dalam menetapkan target makro maupun dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Hagen dan Mundschenk (2002) menegaskan apabila otoritas fiskal berusaha keras untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang diinginkan sedangkan otoritas moneter berusaha keras juga menyerap stimulus fiskal tersebut dalam rangka mencapai target inflasi yang diinginkan, maka konflik ini tidak memberikan hasil yang optimal kecuali kedua kebijakan tersebut berkoordinasi. Hallet (2002) menyimpulkan bahwa regim kebijakan target inflasi dapat mengurangi konflik kebijakan moneter dan fiskal karena antara lain regim target inflasi dapat menggantikan fungsi koordinasi kebijakan dan berfungsi lebih baik dalam perekonomian yang mengalami kejut permintaan. Bhundia dan O’Donnell (2002) menggambarkan interaksi otoritas moneter dan fiskal sebagai hubungan principle-agent, di mana kedua otoritas tersebut memiliki preferensi sama, tidak ada friksi dan tidak terjadi permainan kebijakan. Adanya target inflasi memungkinkan 230 otoritas moneter melakukan kontraksi atas ekspansi kebijakan fiskal yang membahayakan target inflasi. Laurens dan Piedra (1998), menyatakan jika Bank Sentral lebih dominan maka bisa menetapkan secara independen pertumbuhan uang inti tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan keuangan pemerintah. Namun jika pemerintah lebih dominan, maka pemerintah dapat menetapkan besar defisit anggaran tanpa berkonsultasi dengan bank sentral. Selanjutnya jika bank sentral dan pemerintah berperilaku secara independen, maka antara otoritas fiskal dan moneter akan menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten satu sama lain khususnya untuk besarnya defisit anggaran, pertumbuhan uang inti, tingkat inflasi dan suku bunga. Hoa (1986) menyimpulkan bahwa penggunaan kombinasi kebijakan fiskal (pajak) dan moneter (M2) jauh lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dibandingkan menggunakan satu instrumen kebijakan saja. Sargent dan Wallace (1981) menyarankan perlunya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal terkait dengan pihak mana yang akan bergerak duluan (menentukan asumsi makro lebih dulu). Jika otoritas fiskal bergerak dulu, maka kebijakan moneter, harus menyesuaikan. Sebaliknya bila otoritas moneter bergerak dulu, ini berarti otoritas moneter ikut mendorong disiplin kebijakan fiskal. Independensi bank sentral tidak selalu mengakibatkan buruknya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dari sudi literatur tidak diperoleh kejelasan apakah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia bersifat subtitusi atau komplementer. Perkembangan hubungan otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal (Pemerintah) sejak independensi Bank Indonesia tahun 1999 tidak sekuat sebelumnya sehingga semakin perlu diketahui efektivitas interaksi atau koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Apalagi fenomena ekonomi makro akhir-akhir ini tampak mendukung untuk dikaji lebih lanjut interaksi kedua pilar kebijakan makro tersebut. 231 III. Rumusan Masalah Penelitian Pertanyaan penelitian dalam disertasi ini dirumuskan sebagai berikut. (1) Dalam rangka mencapai interaksi kebijakan moneter dan fiskal yang optimal untuk menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output, apakah koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan? (2) Dalam menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output apakah respon kebijakan moneter dan fiskal selama ini sudah optimal?. (3) Untuk mencapai interaksi kebijakan moneter dan fiskal yang optimal, variabel apakah yang perlu diprioritaskan: suku bunga atau output? (4) Bagaimana sifat koordinasi atau interaksi tersebut: apakah bersifat subtitusi (kebijakan moneter ketat-fiskal longgar) atau komplementer (kebijakan moneter ketat-fiskal ketat)? IV. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian interaksi kebijakan moneter dan fiskal ini adalah: (1) mengukur kerugian terkecil dari interaksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output di mana kebijakan fiskal sebagai variabel endogen (ada koordinasi) dibandingkan dengan kebijakan fiskal sebagai variabel eksogen (tidak ada koordinasi). (2) Mengukur apakah interaksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output sudah optimal atau belum. Pengukuran dilakukan dengan menghitung fungsi kerugian terkecil dari minimisasi varian fungsi kerugian variabel inflasi, output dan suku bunga. (3) Melakukan simulasi terhadap respon interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output dengan cara memberikan bobot yang bervariasi antara suku bunga dan output. (4) Mengidentifikasi arah interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia dalam menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output: apakah saling memperkuat (komplemen) atau saling menggantikan (substitusi). 232 V. Landasan Teori Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori New Keynesian mengenai karakeristik model ekonomi makro dan kekakuan harga, Pendekatan ini memiliki pondasi ekonomi mikro yang kuat dan terdapat konsistensi antara ekonomi mikro dengan makro. Teori New Keynesian memiliki elemen-elemen yang mendekati karakteristik perekonomian Indonesia seperti adanya ketidakseimbangan ekonomi yang dipicu oleh kejutan baik di sisi permintaan maupun sisi penawaran serta adanya kekakuan harga dan upah yang ditetapkan di atas biaya marjinal. Gordon (1990) menjelaskan karakteristik utama dari pendekatan newKeynesian sebagai berikut. Pertama, adanya kekakuan harga dan upah dalam jangka pendek sehingga perekonomian tidak dalam keseimbangan, tingkat output rendah dan kurang efisien. Ketidakseimbangan tersebut bersifat persisten sehingga penyesuaian harga menuju kesimbangan menjadi lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama dan diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk interaksi kebijakan moneter dan fiskal untuk membawa perekonomian menuju keseimbangan atau untuk menghindari fluktuasi output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Deviasi output sekarang pada saat harga kaku dengan output pada saat harga fleksibel penuh disebut sebagai kesejangan output (output gap). Secara ekonomi mikro, kesenjangan output digerakkan oleh penetapan harga di atas biaya marjinal. Kedua, adanya perilaku penetapan harga oleh agen ekonomi seperti perusahaan monopoli atau oligopoli. Ketiga, adanya interaksi antar agen ekonomi dan setiap agen ekonomi melakukan optimisasi. Keempat, menggabungkan antara ekspektasi nalar dan optimisasi agen ekonomi. Seseorang dapat dikatakan rasional apabila ia menggunakan semua informasi yang ada, termasuk model yang benar, dalam membentuk ekspektasinya. Dalam menetapkan harga, perusahaan mempertimbangan semua elemen yang terkait di masa yang akan datang seperti ekspektasi inflasi dan mempertahankan rata-rata ekspektasi harga di atas biaya marjinal. Kelima, New Keynesian mengakui mengenai peranan uang dalam menyebabkan 233 inflasi serta peranan pengeluaran sektor swasta dalam mempengaruhi perubahan permintaan agregat. Teori new Keynesian mengenai kurva Phillips dibangun atas dasar kontrak Calvo (Calvo, 1982) di mana inflasi sekarang dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan kesenjangan output sekarang maupun kesenjangan output yang akan datang. Penetapan harga kontrak menyebabkan terjadinya kekakuan harga. Dalam kerangka pengaturan Calvo Pricing, perusahaan mengubah harga pada periode berbeda. Struktur penetapan harga yang berbeda menghasilkan berbagai spesifikasi model kurva Phillips new Keynesian. Beberapa elemen dalam kurva Phillips new Keynesian adalah sebagai berikut (Gali dkk., 2000). Pertama, adanya inflasi yang stabil (steady state) dan biasanya terkait dengan inflasi aktual atau target inflasi. Kedua, inflasi sekarang dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Jika ekspektasi inflasi semakin bermuatan elemen penglihatan ke depan, kurva Phillips akan semakin tegak. Untuk mempengaruhi ekspektasi inflasi ke depan kebijakan moneter harus lebih sistematis, kredibel dan transparan. Ketiga, inflasi sekarang juga dipengaruhi oleh biaya marjinal riil yang merupakan elemen utama bagi perusahaan dalam menetapkan harga. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar tidak sempurna dan menghadapi kurva permintaan ke arah bawah, maka keuntungan maksimal akan dicapai dengan menetapkan mark-up di atas biaya marjinal. Hubungan antara perilaku biaya marjinal individu perusahaan, mark-up dan dinamika inflasi merupakan unsur penting dalam model kurva Phillips new Keynesian yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan agregat. Keempat, parameter yang dibangun dalam kurva Phillips new Keynesian berkaitan langsung dengan perilaku agen ekonomi yang relatif lebih stabil sehingga bebas dari kritikan Lucas. Dalam usahanya untuk mempengaruhi permintaan agregat, kebijakan moneter dan fiskal menghadapi masalah ketidakpastian mengenai struktur ekonomi, ketidakpastian dampak dari kebijakan terhadap perekonomian, goncangan eksogen dalam perkonomian serta pemilihan yang tepat terhadap sasaran kebijakan yang akan dicapai. Dalam mempengaruhi permintaan 234 agregat otoritas moneter dan fiskal memiliki tiga pilihan kebijakan sebagai berikut (Beare,1978:404-406). Pertama, kaidah umpan balik (feedback rule) artinya kebijakan moneter dan fiskal melakukan reaksi terhadap kondisi tertentu perekonomian. Kaidah umpan balik Keynes dengan target output akan mendorong inflasi biaya namun dapat mencegah fluktuasi harga dan output akibat adanya goncangan permintaan agregat. Kaidah umpan balik Keynes untuk target harga akan mencegah inflasi biaya walaupun dengan biaya resesi yang lebih besar dibandingkan kaidah moneter. Kedua, kebijakan diskresi yakni melakukan reaksi dengan cara unik atau khusus terhadap suatu kondisi perekonomian tertentu dengan menggunakan semua informasi yang tersedia maupun kesalahan kebijakan di masa lalu. Kebijakan diskresi adalah kebijakan konsisten menurut waktu (time consistentcy) dan cenderung mencoba memaksimalkan kesejahteraan sosial pada tingkat ekspektasi tertentu. Selain itu, insentif untuk merubah kebijakan diskresi di masa mendatang akan terjadi jika terdapat perubahan kondisi perekonomian. Ketiga, kaidah tetap (fixed rule) yakni menetapkan suatu kaidah secara independen tanpa mempersoalkan kondisi perekonomian seperti kaidah Friedman (menganjurkan perlunya menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar pada angka yang stabil tanpa memperhatikan kondisi perekonomian), kaidah McCallum (1988) dan Taylor (1993). VI. Model Dynamic Stochastic General Equilibirum (DSGE) Penelitian ini menggunakan model struktural ekonomi makro yakni model keseimbangan umum yang dinamis atau DSGE yang didasarkan pada paradigma new Keynesian dan memasukkan spesifikasi forward looking untuk model makro yang memiliki landasan mikro dan spesifikasi backward looking untuk model makro yang tidak memiliki landasan mikro serta didasarkan pada kaidah moneter dan kaidah fiskal. Wicken (2008:46) menyatakan bahwa model DSGE ingin menjelaskan perilaku dinamis perekonomian pada model keseimbangan dan bagaimana reaksinya terhadap perubahan variabel eksogen dan goncangan. Selain itu, model DSGE adalah 235 model antar-waktu (inter-temporal) dan forward looking artinya keputusan sekarang dipengaruhi oleh ekspektasi mendatang sehingga model DSGE menggunakan optimisasi dinamis antar waktu. Untuk meneliti interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia digunakan model DSGE yang didasarkan pada Gali dan Monaceli (2005). Model DSGE untuk perekonomian terbuka yang terdiri dari persamaan output yang menggambarkan sisi permintaan agregat, persamaan inflasi yang mencerminkan sisi penawaran agregat, persamaan suku bunga nominal untuk kaidah moneter, persamaan pengeluaran pemerintah dan persamaan pajak untuk kaidah fiskal serta persamaan-persamaan untuk mewakili keterbukaan ekonomi yakni persamaan nilai tukar nominal, persamaan otoregresi untuk terms of trade, output luar negeri dan inflasi luar negeri. 1. Persamaan Output mewakili Sisi Permintaan 2. Persamaan Kurve Phillips mewakili Sisi Penawaran 236 3. Persamaan Sektor Luar Negeri (nilai tukar nominal, terms of trade, output luar negeri dan inflasi luar negeri) 4. Kidah Moneter 237 5. 238 Kaidah Fiskal VII. Estimasi Parameter Model DSGE Estimasi parameter dalam model ini menggunakan pendekatan estimasi Bayesian, di mana salah satu keunggulan dalam pendekatan ini adalah dapat menggabungkan antara data dengan tambahan informasi terhadap suatu parameter melalui suatu prior distribution. Estimasi parameter model dilakukan dengan metode Bayesian sedangkan perhitungan posterior menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo yang dikombinasikan dengan metode Metropolis Hasting untuk menambah data sample agar diperoleh nilai modus yang sesungguhnya. Setelah itu, dilakukan uji konvergensi untuk mendeteksi apakah varians betweensequence (varians antara urutan simulasi dengan urutan simulasi lain secara parallel) tidak lebih besar dari varians within-sequence (varian setiap satu urutan simulasi). Estimasi Bayesian (Bayes theorem) ingin menggambarkan tingkat kepercayaan seorang individu dalam kondisi ketidakpastian dan bagaimana individu tersebut seharusnya bersikap guna menghindari tindakan yang tidak konsisten. Estimasi Bayesian memerlukan informasi awal atau distribusi prior dalam melakukan estimasi terhadap suatu parameter yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penentuan parameter yang kemudian dipakai sebagai means atau modes pada prior density yang akan dibentuk, sedangkan unsur ketidakpastiannya diekspresikan dengan menentukan varians yang tepat untuk prior density tersebut. Dengan demikian, estimasi Bayesian memerlukan informasi sampel dan informasi awal. Asumsi dan informasi awal kemudian dimasukkan ke dalam proses inferensi guna menghasilkan posterior densities dari parameter-parameter yang digunakan di dalam model serta predictive densities untuk keperluan proyeksi. VIII. Fungsi Kerugian Untuk menjawab kebijakan moneter yang optimal terhadap beberapa skenario kebijakan fiskal, digunakan standard optimal control approach dan 239 fungsi kerugian antar waktu (Rudebusch dan Svensson, 1999). Pertama, untuk mencapai tujuan kebijakan dalam kerangka target inflasi dapat menggunakan model fungsi kerugian yakni suatu fungsi kuadrat pada variabel inflasi dan variasi kesenjangan output. Kedua, dengan model kurve output dan kurve Phillips tersebut di atas, kita dapat menetapkan kaidah target inflasi (inflation targeting rule) dengan menggunakan fungsi kerugian. Ketiga, bank sentral dapat menetapkan suku bunga sedemikian rupa sehingga fungsi kerugian antar-waktu menjadi terkecil. di mana : πt adalah tingkat inflasi periode t yt adalah output periode t it adalah suku bunga periode t )i adalah parameter fungsi kerugian Selanjutnya dilakukan simulasi kebijakan moneter optimal dalam menghadapi goncangan output dan inflasi dengan tiga variasi bobot pada suku bunga dan output. Diambil dua skenario kaidah kebijakan optimal yaitu kebijakan fiskal sebagai variabel endogenous dan kebijakan fiskal sebagai variabel eksogenous. Untuk simplifikasi, hanya diambil respon kebijakan moneter akibat goncangan sementara pada output dan inflasi dengan 3 skenario bobot pada variabel suku bunga dan output sebagai berikut. Pertama, kaidah kebijakan optimal I di mana output dan suku bunga memiliki bobot yang sama dalam fungsi kerugian yaitu )1= )2. Kedua, kaidah kebijakan optimal II di mana bobot output ()1=1) lebih besar dibandinglan bobot suku bunga dalam fungsi kerugian ()2=0.5). Ketiga, kaidah kebijakan optimal III di mana bobot suku bunga ()2=0.5) lebih besar dibandingkan bobot output dalam fungsi kerugian ()1=0.1). 240 IX. Hasil Simulasi Reaksi Impuls terhadap Goncangan Eksogen Hasil simulasi reaksi impulse mencerminkan perilaku optimal pelaku ekonomi terhadap goncangan eksogen dan selanjutnya menguji apakah mekanisme hubungan antar variabel dalam model relatif koheren secara teoiritis. Beberapa aspek penting dalam simulasi reaksi impulse adalah pertama, perekonomian diasumsi berada pada kondisi keseimbangan jangka panjang, namun terdapat goncangan yang mengakibatkan perekonomian keluar dari keseimbangannya. Jika goncangan tersebut bersifat sementara, maka keseimbangan tersebut akan kembali pada kondisi semula namun jika goncangan tersebut bersifat permanen akan menggeser keseimbangan perekonomian tersebut secara permanen. Kedua, goncangan-goncangan di dalam reaksi impulse merupakan goncangan yang tidak terantisipasi sebelumnya, namun setelah terjadi, goncangan-goncangan tersebut dipahami secara lebih jelas dan baik oleh para pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ketiga, setiap goncangan merupakan goncangan individu yang terjadi hanya pada satu variabel saja. Keempat, hasil reaksi impulse dalam model DGE ini adalah nilai prosentase (basis point) untuk variabel inflasi dan nilai prosentase deviasi dari steady state-nya untuk variabel output.4 Untuk melihat arah interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia apakah bersifat substitusi atau komplemen, disimulasikan dua goncangan dalam model yakni goncangan sementara inflasi yang umumnya berasal dari goncangan cost push dan goncangan sementara ouput yang berasal dari goncangan permintaan. Dalam simulasi ini, sebelum dilakukan goncangan, seluruh variabel akan bernilai nol (nilai persentase deviasi terhadap steady state-nya adalah nol) yang berarti bahwa seluruh variabel berada dalam nilai steady state. Untuk masing-masing variabel inflasi dan output kemudian diberikan goncangan pada awal periode untuk menghasilkan reaksi impulse, dimana setiap variabel akan bereaksi terhadap goncangan tersebut. 4 Hasil nilai untuk inflasi merupakan nilai sebenarnya atau, St=St namun untuk suku bunga ( iˆt { it i 1 i ) dan variabel-variabel lainnya ( Xˆ t { X t X X { OQ X t OQ X ), merupakan deviasi dari nilai steady state 241 Goncangan inflasi (variabel pi) berupa kenaikan inflasi sementara sebesar 1 persen diawal periode sebagai akibat peningkatan biaya produksi (grafik 9.1)5. Peningkatan inflasi ini akan dibarengi dengan adanya peningkatan output dari sisi permintaan dan hal ini menggambarkan adanya trade off antara inflasi dan output. Sebagai bank sentral yang berorientasi kuat pada pengendalian inflasi dengan kerangka target inflasi, maka peningkatan inflasi yang berakibat pada peningkatan kesenjangan inflasi selanjutnya akan direspon bank sentral dengan meningkatkan suku bunga kebijakan (variabel ir) pada periode pertama. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah akan menurunkan pengeluarannya (variabel g) karena output (variabel y) dianggap sudah cukup meningkat. Menurunnya output pada gilirannya akan menurunkan pajak. Grafik 9.1: Goncangan Inflasi 5 Kenaikan inflasi 1% pada grafik 9.1 adalah mulai dari nol ke angka 1. Demikian juga pada grafik 9.2 kenaikan output 1% adalah dari angka nol ke angka 1. Untuk variabel yang lain cara membacanya sama yaitu mulai dari nol (titik origin). 242 Dalam simulasi ini goncangan output berupa kenaikan output (variabel y) secara temporer sebesar 1 persen diawal periode sebagaimana terlihat pada grafik 9.2. Goncangan output dapat diartikan sebagai peningkatan permintaan terhadap barang sehingga menyebabkan peningkatan output. Peningkatan output dari sisi permintaan ini juga dibarengi dengan adanya peningkatan inflasi (inflasi permintaan), namun peningkatan inflasi tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan output yang ada. Sebagai bank sentral yang berorientasi kuat pada pengendalian inflasi dengan kerangka target inflasi, maka peningkatan inflasi yang relatif kecil tersebut tidak terlalu direspon, bahkan untuk lebih meningkatkan output dari sisi penawaran agar permintaan terpenuhi, bank sentral cenderung untuk menurunkan suku bunganya (variabel ir). Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah akan tetap mengurangi pengeluarannya (variabel g) karena output dari sisi permintaan dianggap sudah cukup meningkat. Grafik 9.2: Goncangan Output 243 Dari hasil simulasi tersebut dapat diketahui reaksi kebijakan moneter dan fiskal terhadap goncangan sebagai berikut. Pertama, jika terjadi goncangan inflasi berupa kenaikan inflasi 1%, interaksi kebijakan moneter dan fiskal bergerak searah atau komplementer yakni otoritas moneter akan menaikkan suku bunga dan otoritas fiskal akan menurunkan pengeluarannya. Kedua, jika terjadi goncangan output berupa kenaikan output sebesar 1%, interaksi kebijakan fiskal dan moneter bergerak ke arah yang berlawanan atau subtitusi yakni otoritas fiskal akan menurunkan pengeluarannya dan otoritas moneter akan menurunkan suku bunga. Dengan demikian interaksi kedua instumen kebijakan bergantung pada tipe goncangan yang terjadi dalam sistem dan pada stuktural model yang dipasangkan pada data. X. Hasil Analisis Fungsi Kerugian Untuk mengukur apakah interaksi kebijakan moneter dan fiskal selama periode observasi optimal atau belum, dilakukan analisis fungsi kerugian antar waktu dengan menggunakan hasil estimasi parameter pada saat kebijakan fiskal bersifat endogen dan eksogen. Kebijakan fiskal bersifat endogen mengandung arti bahwa terjadi interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal, sedangkan kebijakan fiskal bersifat eksogen mengandung arti bahwa tidak ada interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal. Tabel 10.1: Fungsi Kerugian tiap Kaidah Kebijakan Optimal: No Goncangan 1 Kebijakan Fiskal Endogen Goncangan output Goncangn inflasi 2 Kebijakan Fiskal Eksogen Goncangan output Goncangan inflasi 244 Fungsi Kerugian Kaidah Kebijakan Optimal I II III 0.6184 1.5831 0.5898 1.4576 0.0851 1.4517 0.9946 1.537 0.9402 1.4163 0.1431 1.407 Tabel 10.1 menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal (kebijakan fiskal endogen) lebih efektif dalam menghadapi goncangan output dibandingkan tanpa koordinasi (kebijakan fiskal eksogen). Hal ini ditunjukkan oleh fungsi kerugian yang lebih kecil dalam menghadapi goncangan output apabila ada koordinasi. Kebijakan fiskal endogen akan mempermudah aturan kebijakan untuk menggiring output kembali normal (countercyclical role of fiscal policy) dan tidak membuat kerugian sosial. Kedua, dalam menghadapi goncangan inflasi kebijakan fiskal eksogen (tidak ada koordinaasi) ternyata memberikan fungsi kerugian lebih kecil dibandingkan kebijakan fiskal endogen (ada koordinasi). Hal ini memberikan implikasi bahwa koordinasi moneter dan fiskal masih perlu ditingkatkan secara berarti dalam menghadapi goncangan inflasi. Ketiga, dalam menghadapi goncangan ekonomi (ouput maupun inflasi, kebijakan fiskal endogen maupun eksogen), terdapat kecenderungan bahwa semakin kecil varian suku bunga, relatif terhadap varian output, semakin kecil kerugian sosial yang ditimbulkannya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai kerugian yang selalu lebih kecil pada kaidah III dibandingkan kaidah I dan II. XI. Optimalisasi Fungsi Kerugian Dalam analisis fungsi kerugian di atas diperoleh hasil bahwa pada saat terjadi goncangan output interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal sudah efektif. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah interaksi kebijakan moneter dan fiskal tersebut sudah optimal atau belum. Untuk menjawab hal ini dilakukan penggeseran nilai parameter dalam persamaan kebijakan moneter (Taylor rule) serta kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) dan mencari nilai fungsi kerugian yang paling minimum setelah dilakukan simulasi stochastic pada goncangan tertentu. Pada persamaan Taylor rule beberapa parameter yang nilainya digeser antara lain UR yang menggambarkan tingkat penghalusan suku bunga \1 245 yang merupakan bobot relatif kesenjangan inflasi, \2 yang merupakan bobot relatif kesenjangan output dan \3 yang merupakan bobot relatif kesenjangan nilai tukar rupiah. Penggeseran parameter dilakukan dengan mengkombinasikan dua parameter yaitu parameter penghalusan suku bunga ( UR ) yang dikombinasikan dengan masing-masing bobot relatif tersebut di atas. Selanjutnya untuk persamaan pengeluaran pemerintah beberapa parameter yang nilainya digeser adalah G11 yang merupakan derajat penghalusan dari pengeluaran pemerintah, G20 yang merupakan parameter respon pengeluaran pemerintah terhadap output, G21 yang merupakan parameter respon pengeluaran pemerintah (lag) terhadap output dan ]1 yang merupakan parameter respon pengeluaran pemerintah terhadap defisit anggaran. Seperti halnya pada persamaan Taylor rule, penggeseran parameter dilakukan dengan mengkombinasikan dua parameter yaitu parameter penghalusan pengeluaran pemerintah ( G11 ) yang dikombinasikan dengan masing-masing parameter respon pengeluaran pemerintah tersebut di atas. Dengan mengkombinasikan dua parameter kemudian dilakukan simulasi stochastic pada gonncangan output dan goncangan inflasi, maka secara grafis fungsi kerugian dapat digambarkan secara tiga dimensi seperti yang terlihat pada grafik permukaan fungsi kerugian untuk tiap-tiap kombinasi parameter sebagai berikut. 246 Grafik 11.1: Goncangan Inflasi: Kebijakan Fiskal Indogen (bobot output sama dengan bobot suku bunga) Grafik 11.1 di atas menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai kombinasi parameter derajad penghalusan pengeluaran pemerintah (delta11) dan respon pngeluaran pemerintah terhadap output (delta20), di mana kebijakan fiskal bersifat endogen dan bobot suku bunga dan output sama, maka kombinasi parameter tersebut dalam menghadapi goncangan inflasi akan menghasilkan fungsi kerugian terkecil sebesar 1,5865. Kaidah fungsi kerugian tersebut tetap menggunakan tiga macam kaidah fungsi kerugian kebijakan optimal I,II dan III berdasarkan bobot yang diberikan terhadap masing-masing varian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga untuk tiap-tiap kombinasi parameter akan dihasilkan tiga macam grafik permukaan fungsi kerugian. Apabila fungsi kerugian tersebut dicari nilai minimumnya untuk tiap-tiap kombinasi parameter yang ada, maka akan diperoleh tabel sebagai berikut. 247 Tabel 11.1: Fungsi Kerugian Untuk Tiap Kombinasi Parameter Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik: data diolah. Tabel 11.1 tersebut di atas menjelaskan temuan-temuan sebagai berikut. Pertama, Tampak bahwa dengan menggunakan kombinasi parameter suku bunga dan parameter pengeluaran pemerintah dalam fungsi kerugian, semua fungsi kerugian yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan menggunakan parameter hasil estimasi sebelumnya. Hal ini berarti bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal belum optimal karena nilai fungsi kerugian pada parameter hasil estimasi secara mutlak masih lebih besar jika dibandingkan dengan fungsi kerugian pada kombinasi parameter yang ada. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal masih perlu untuk ditingkatkan guna memperkecil kerugian sosial. Kedua, dalam menghadapi goncangan output kombinasi parameter kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) ternyata memberikan fungsi kerugian yang jauh lebih kecil dibandingkan kombinasi parameter kebijakan moneter (suku bunga). Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam menghadapi goncangan output, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap diperlukan, namun penggunaan instrumen kebijakan fiskal lebih dikedepankan dibandingkan instrumen kebijakan moneter. Ketiga, sebaliknya dalam menghadapi goncangan inflasi kombinasi parameter kebijakan moneter ternyata memberikan fungsi kerugian yang lebih kecil dibandingkan kombinasi 248 parameter kebijakan fiskal. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam menghadapi goncangan inflasi, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap diperlukan, namun penggunaan instrumen kebijakan moneter lebih diprioritaskan dibandingkan instrumen kebijakan fiskal. Keempat, tabel 11.1 di atas juga menghasilkan kecenderungan bahwa semakin kecil varian variabel suku bunga relatif terhadap variabel output, semakin kecil kerugian yang dihasilkan. Implikasi dari hal ini adalah penggunaan instrumen suku bunga secara tepat sasaran dan tepat waktu akan memperkecil kerugian sosial yang berarti. XII. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan permasalahan, tujuan dan hipotesa penelitian interaksi kebijakan moneter dan fiskal yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan hasil perhitungan parameter model, hasil simulasi reaksi impulse terhadap goncangan inflasi dan ouput dan analisa dan optimalisasi fungsi kerugian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghadapi goncangan inflasi dan goncangan output, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal lebih bermafaat, dibandingkan tanpa koordinasi, dalam rangka mengurangi kerugian sosial. Hasil simulasi membuktikan adanya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal (kebijakan fiskal endogen) menghasilkan fungsi kerugian yang lebih kecil dibandingkan tanpa koordinasi (kebijakan fiskal eksogen). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan seperti adanya semacam Dewan Moneter. 2. Menghadapi goncangan inflasi respon kebijakan moneter dan fiskal belum optimal. Hasil simulasi memperlihatkan fungsi kerugian yang lebih besar jika kebijakan fiskal bersifat endogen dibandingkan fungsi kerugian apabila kebijakan fiskal bersifat eksogen. Sebaliknya dalam menghadapi goncangan output interaksi kebijakan moneter dan fiskal (kebijakan fiskal endogen) menghasilkan fungsi kerugian yang lebih kecil dibandingkan fungsi kerugian apabila kebijakan fiskal bersifat eksogen, untuk semua variasi bobot suku bunga dan ouput. Sementara 249 itu, respon kebijakan moneter dan fiskal terhadap goncangan inflasi dan goncangan output secara bersama-sama terbukti juga belum optimal karena nilai fungsi kerugian pada parameter hasil estimasi secara mutlak masih lebih besar jika dibandingkan dengan fungsi kerugian pada kombinasi parameter yang ada. 3. Untuk mencapai interaksi kebijakan moneter dan fiskal yang optimal volatilitas atau varian suku bunga perlu dijaga seminimal mungkin relatif terhadap varian output. Dalam simulasi terbukti bawa semakin kecil varian suku bunga relatif terhadap variabel output akan menghasilkan fungsi kerugian yang lebih kecil. 4. Interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia ke subtitusi atau komplementer dipengaruhi oleh tipe goncangan. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia dalam periode observasi bersifat komplementer atau saling membantu dalam hal menghadapi goncangan inflasi. Sebaliknya interaksi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bersifat subtitusi atau saling menggantikan dalam menghadapi goncangan output. Goncangan inflasi berupa kenaikan inflasi 1% akan mendorong otoritas moneter meningkatkan suku bunga kebijakan untuk mengendalikan inflasi sedangkan otoritas fiskal akan mengurangi pengeluaran pemerintah atau defisit anggaran karena output dianggap sudah cukup meningkat. Goncangan output berupa kenaikan output sebesar 1% otoritas moneter tidak akan menaikkan suku bunga kebijakan karena kenaikan output tersebut tidak menimbulkan dampak inflasi yang signifikan sedangkan otoritas fiskal akan mengurangi pengeluarannya karena menganggap ouput sudah cukup meningkat. Berdasarkan atas simpulan dari penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut. 1. 250 Mengingat interaksi kebijakan moneter dan fiskal menghasilkan fungsi kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan tanpa interaksi kebijakan moneter dan fiskal, serta interaksi kebijakan moneter dan fiskal belum optimal berdasarkan kombinasi parameter, disarankan pembentukan Dewan Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal (semacam Dewan Moneter) guna meningkatkan bauran kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Misalnya, bauran kebijakan suku bunga dengan kebijakaan pajak dalam rangka mncapai output yang optimal, kebijakan nilai tukar rupiah dengan kebijakan perdagangan dalam mendorong ekspor dan impor, kebijakan perbankan dengan kebijakan sektor pertanian dalam rangka stabilisasi harga dan peningkatan kapasitas ekonomi, kombinasi kebijakan suku bunga dengan kebijakan pengeluaran pemerintah dalam rangka mendorong output dan stabilisasi harga, Adanya bauran kebijakan moneter dan fiskal disertai pengutan kelembagan tersebut (Dewan Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal) diharapkan dapat meningkatkan output dan stabilisasi harga yang lebih optimal dalam rangka memerangi kemiskinan di Indonesia. 2. Oleh karena interaksi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia belum efektif dalam menghadapi goncangan inflasi dibandingkan terhadap goncangan output, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam memerangi tekanan inflasi dari sisi penawaran perlu ditingkatkan. Misalnya pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka mengendalikn inflasi dari sisi penawaran. Selain itu, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi melalui sisi penawaran. Juga penguatan lembaga seperti Bulog perlu ditingkatkan perannya dalam rangka pengendalian harga beras dan komoditas inflasi lainnya. 3. Dalam rangka menghadapi goncangan inflasi dan output, interaksi kebijakan moneter dan fiskal seyogyanya memberikan prioritas lebih besar kepada variabel suku bunga dibandingkan variabel output karena memberikan fungsi kerugian yang lebih kecil dibandingkan memberikan prioritas yang lebih besar pada output. Volatilitas atau varian suku bunga perlu dijaga seminimal mungkin relatif terhadap 251 varian atau volatilitas output. Contoh, sumber inflasi yang berasal dari sisi penawaran hendaknya tidak direspon dengan kenaikan suku bunga sementara untuk meningkatkan output dalam masa resesi atau pemulihan ekonomi diperlukan penurunan suku bunga yang terukur. Selanjutnya, sumber inflasi yang bersumber dari ekspektasi perlu direspon dengan kenaikan suku bunga yang terbatas. 252 Lampiran 1: Parameter dalam Model DSGE yang akan diestimasi 253 Lampirn 2: Hasil Estimasi Parameter dalam Model DSGE Dari 19 parameter yang sudah diestimasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Pertama adalah parameter output terdiri dari alpha, sigma, beta dan phi. Parameter alpha = 0,73 mencerminkan tingkat keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap luar negeri, semakin terbuka perekonomian semakin besar parameter alpha. Parameter sigma=0,97 menggambarkan elastisitas terbalik substitusi antar waktu. Kedua adalah parameter inflasi yang terdiri dari theta dan phil. Parameter theta=0,87 merefleksikan tingkat rigiditas harga sedangkan parameter phil=0,91 adalah elastisitas terbalik penawaran tenaga kerja. Ketiga adalah parameter suku bunga terdiri dari rhor, psipi. psy dan psie. Parameter rhor= 0,44 mencerminkan tingkat penghalusan suku bunga sementara parameter psipi=0,80 adalah respon inflasi. Keempat adalah parameter terms of trade, output luar negeri dan inflasi luar negeri (rhos, rhoyf dan rhopif ) merupakan koefisien autoregresif dari masing-masing variabel tersebut. Kelima adalah parameter pengeluaran pemerintah terdiri dari delta11, delta 20, delta22 dan zeta1. Parameter delta11=0,62 adalah tingkat penghalusan variabel pengeluaran pemerintah. Keenam adalah parameter pajak yaitu theta11, theta20, theta21 dan zeta 2. Parameter theta11=0,82 adalah tingkat penghalusan pajak. 254 DAFTAR PUSTAKA Abel A., 2002, The Philadelphia Fed Policy Forum: Summary of the 2001 Policy Forum and Announcement of the 2002, Editor: Loretta J., Policy Forum, Business Forum, Q3. Adam K. dan Billi R.M., 2005, Monetary and Fiscal Interaction without Commitment and the Value of Monetary Conservatism, European Central Bank Research Department, Frankfurt, Germany. Artis J.A.,1989, Macroeconomics, Oxford University Press, New York. Baldacci E., Hillman A.L. dan Kojo N.C., 2003, Growth, Governance and Fiscal Policy Transmission Channels in Low-Income Countries, IMF Working Paper, WP/3/237: 1-38. Beetsma, R.M.W.J. and Jensen, H., 2002, Monetary and Fiscal Policy Interactions in a Micro-Founded Model of a Monetary Union, European Central Bank, Working Paper Series, No. 166. Bennet, H. and Loayza N., 2000, Policy Biases when Monetary and Fiscal Authorities have Different Objectives, Central Bank of Chile Working Papers, No. 66 Bennett, H. and Loayza, N., 2005, Fiscal and Monetary Policy Biases under Lack of Coordination, World Bank. Bhundia A dan O,Donnell G., 2002, UK Policy Coordination: The Importance of Institutional Design, Fiscal Studies, Volume 23 No. 1:135-164. Blinder Alan S., 1982, Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy, NBER Working Paper Series, September, No.982. Blinder A., 1991, Why are Prices Sticky? Preliminary Result From an Interview Study, American Economic Review, Mei, No.81:89-96. Brimmer, A.F. dan Sinai A., 1986, The Monetary-Fiscal Policy Mix: Implication for the Short Run, The American Economic Review, May, Vol. 76. No.2: 203-208. Boyes and Malvin, 2005, Economics, Houghton Mifflin Company, Edisi ke-6. 255 Brooks and Gelman, 1998, General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations, Journal of Computational and Graphical Statistics, Vol. 7, No. 4: 434-455. Calvo, G.,1983, Staggered Price in a Utility-maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, 12(3):383-398. Chari V.V. dan Keheo P.J., 1999, Optimal Fiscal and Monetary Policy, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper Series, No.6891. Chari V.V., Chistianto L.J. dan Keheo P.J., 1996, Optimality of the Friedman Rule in Economies with Distorting Taxes, Journal of Monetary Economics, Vol 37:203-223. Chip and Greenberg, 1995, Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm, The American Statistician, November 1995, Vol.49, No.4: 326-335. Christiano , L.J. dan Fitzgerakd , T.J., 2000, Understanding the Fiscal Theory of the Price Level, Economic Review, Volume 36, No. 2. Cecchetti S., 1986, The Frequency of Price Adjustment: A Study of the Newsstand Prices of Magazines, Journal of Econometrics, April, No. 31: 255-74. Clarida, R., J. Gali, and M. Gertler, 1998, Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence, European Economic Review, Vol. 42, No. 6: 1033-1067. Dixit, A. dan Lamberti L., 2003, Symbiosis of Monetary and Fiscal Policies in a Monetary Union, Journal of International Economics, Volume 60: 235-247. Dornbusch R., Fisher S. dan Startz R., 1998, Macroeconomics, Irwin McGraw-Hill, USA. Dodge D., 2002, The Interaction Between Monetary and Fiscal Policies, Canadian Public Policy, Vol.28:187-201. Froyen R.T., 1996, Macroeconomics: Theories and Policies, Prentice Hall Incorporation, USA. 256 Fisher S.,1977, Long-term Contract, Rational Expectation, and the Optimal Money Supply Rule, Journal of Political Economy, No.85:191205. Friedman, M., 1968, The Role of Monetary Policy, American Economic Review, Volume 58, No. 1 (March):1-17. Gali J. dan Gertler M., 1999, Inflation Dynamics: A struktural Econometric Analysis, Journal of Monetary Economics, Vol. 44, No. 2:195222 Gali, J., Gertler M. dan D. Lopez-Salido, 2001. “European Inflation Dynamics”. European Economic Review, Vol. 45, no. 7:1237-1270. Gali, J., dan Monacelli T., 2005, Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy, Review of Economic Studies, Vol.72 No.252: 707-734 Gelfand, A.E. dan Smith, A.F., 1990, Sampling Based Approach to Calculating Marginal Densities, Journal of the American Statistical Association, Vol. 85:398-409. Gelman A. dan Rubin D.B., 1992, Inference from Iterative Simulation Using Multiple Sequences, Statistical Science, No.7:433-438. Geman, S. and D. Geman (1984), Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions and the Bayesian Restoration of Images, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.6:721-741. Giannomi M.P. dan Woodford M., 2000, Optimal Interest Rate Rule: Application, National Bureau of Economic Research (NBER), No.9420. Gordon R.J., 1990, What is New-Keynesian Economics?, Journal of Economic Literature, 28:1115-71. Goyal, A., 2002, Coordinating Monetary and Fiscal Policies, India Development Report (editor Parikh, K.S. dan Radhakrisha R.), IGUDR dan Oxford University Press. Greenwald B. dan Stiglitz J., 1993, New and old Keynesian, Journal of Economic Perspectives, Winter, No.7:23-44. 257 Hagen J.V. dan Mundschenk S., 2002, Fiscal and Monetary Policy Coordination in European Monetary Union (EMU), Central Bank of Chile Working Papers, Desember, No. 194. Hallett, A.H., 2002, Inflation Targeting as a Coordination Device, Open Economies Review, Volume 13: 341-362. Hasting, W.K. (1970), Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and their Applications, Biometrica 57:97-109. Hoa, T.V., 1986, Effects on Monetary dan Fiscal Policy on Inflation: Some evidence from the J-Test, Economics Letters, Volume 22:187-190. Iwamoto, Y., 2005, Interaction between Monetary and Fiscal Policy and the Policy Mix Theoretical Consideration and Japanese Experience, Center of International Research on the Japanese Economy, Faculty of Economics, University of Tokyo, Japan, No. F-365. Javed, Z.H. dan Sahinoz, A., 2005, Interaction of Monetary and Fiscal Policy to Case of Turkey, Journal of Applied Sciences, No.5 (2): 220226. Kimball, M.S.,1995,The Quantitative Analytics of the Basic Neo-Monetarist Model, Journal of Money, Credit and Banking, 27(4):12411277. Kocherlakota N. dan Phelan C. (1999): Explaining the Fiscal Theory o Price Level, Federal Reseve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol.3 No.4:14-23. Laurens, B. dan Piedra, L., 1998, Coordination of Monetary and Fiscal Policies, IMF Working Paper, WP/98/25, International Monetary Fund, Washington D.C. Leitemo, K. (2004): A Game between the Fiscal Policy and the Monetary Authorities Under Inflation Targeting, European Journal of Political Economy, Volume 20:709-724. Leith, C. dan Malley J., 2003. Estimated Open Economy New-Keynesian Phillips Curves for the G7, CESifo Working Papers, No. 834. 258 Less, K., Matheson T. dan Smith S., 2007, Open Economy DESGE-VAR forecasting and Policy Analysis: Head to head with the RBNZ published forecasts, Discussion Paper Series, Reserve Bank of New Zealand.. Lipsey, R.G.,1960, The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rate in the UK 1962-1957: A Further Analysis, Economica, Volume 27:1-31. Liu, P., 2006, A Small New Keynesian Model of the New Zealand Economy, Discussion Paper Series, DP2006/03, Reserve Bank of New Zealand. Lubik, T. dan Schorfheide F., 2005, Do Central Banks Respond to Exchange Rate Movements? A Struktural Investigation, Manuscript, Department of Economics, University of Pennsylvania. Lubik, T. dan Schorfheide F, 2005, A Bayesian Look at New Open Economy Macroeconomics, Manuscript, Department of Economics, University of Pennsylvania. Lucas, R.E.Jr.,1972, Expectation and the Neutrality of Money, Journal of Economic Theory, No.4:103-124. Lucas, R.E. Jr.,1976, Economic Policy Evaluation: A Critique, CanergieRochester Conference Series on Public Policy No.62:19-46. Mankiw N.G., 2003, Macroeconomics, Worth Publisher, New York. Mankiw N.G, Kneebone R.D., McKenzie K.J dan Rowe N.,2005, Principles of Macroeconomics, Nelson A Division of Thomson Canada Limited, Second Edition. Maryatmo, R., 2004, Dampak Moneter Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah dan Peranan Asa Nalar dalam simulasi Model Makro Ekonomi Indinesia:1983.1-2002.4, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. McCallum, B.T., 1988, Robustness Property of Rule for Monetary Policy, Carnegie-Rochester Conference Series Public Policy, 29: 17-204. 259 Metropolis N., Rosenbluth, A.W., Rosenbluth, M.N., Teller, A.H. and Teller, E., 1953, Equations of the State Calculations by Fast Computing Machines, Journal of Chemical Physics,No. 21:1087-1092. Mochtar F., 2004, Fiscal and Monetary Interaction: Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia, Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September:359-386. Mohanty M.S. dan Scatigna M.,2003, Countercyclical Fiscal Policy and Central Bank, BIS Papers , No. 20. Muscatelli A., Tirelli P. and Trecroci C., 2004, Fiscal and Monetary Policy Interactions: Empirical Evidence and Optimal Policy using a Structural New-Keynesian Model. Journal of Macroeconomics, Vol. 26 (2): 257-280. Muscatelli, A., P. Tirelli and C. Trecroci, 2003, The Interaction of Fiscal and Monetary Policies: Some Evidence using Structural Model, CESifo Working Paper, No. 1060. Muscatelli, A., P. Tirelli and C. Trecroci, 2001. “Monetary and Fiscal Policy Interactions over the Cycle: Some Empirical Evidence”. Forthcoming in R. Beetsma, C. Favero, A. Missale, V.A. Muscatelli, P. Natale and P. Tirelli (eds.), Fiscal Policies, Monetary Policies And Labor Markets. Key Aspects of European Macroeconomics Policies after Monetary Unification, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Olafsson T.T, 2006, The New Keynesian Phillips Curve; In Search of Improvement and Adaption to the Open Economy, Central Bank of Iceland Working Paper, No.31, Economics Department, September:177. Orphanides, A., 2003, Historical Monetary Policy Analysis and the Taylor Rule, Journal of Monetary Economics, Volume 50:983-1022. Phelp, E.S., 1968, Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium, Journal of Political Economy, Volume 76, Number 678. Rahutami A. I.,2007, Interaksi Sektor Moneter dan Fiskal di Indonesia Tahun 1980.1-2006.4 Pendekatan Sistem Ekonomi Simultan, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 260 Ramsey F.P.,1927, A Contribution to the Theory of Taxation, Economic Journal, Vol.37: 47-61. Reynolds, A.,2001, The Fiscal-Monetary Policy Mix, Cato Journal, Volume 21(2): 263-275. Rozkrut M., 2003, The Monetary and Fiscal Policy Mix in Poland, BIS Paper, No.20, Oktober :214-217. Rudebusch, G.D. and Svensson, L.E.O., 1999. Policy Rules for Inflation Targeting. In Taylor, J. B. ed., 1999, Monetary Policy Rules, University of Chicago Press. Sargent, T.J.,1971, A Note on the Accelerationist Controversy, Journal of Money, Credit, and Banking, No.3:721-725. Sargent, T.J. dan Wallace N., 1981, Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 5(3):1-17. Simorangkir I., 2005, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan menggunakan pendekatan Game Theory, Bank Indonesia PPSK Working Paper Series, No. WP/02/1005. Smets F. dan Wouters R., 2004, An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Euro Area, Journal of the European Economic Association, 1(5):1123-1175 Smith, W.L.,1957, Monetary-Fiscal Policy and Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, May, Volume 71. No.1. Smith, A.F.M dan Robert, G.O., 1993, Bayesian Computation via the Gibb Sampler and Related Markov Chain Monte Carlo Methods, Journal of Royal Statistical Society, Series B, Volume 55: 3-24. Snowdon B., Vane H., dan Wynarczyk P.,1995, A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, the UK. Stevenson,L., 2002, Are There Limit to the Use of Monetary Policy for Economic Stabilization?, Rethinking Stabilization Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City. 261 Stevenson A., Muscatelli V. dan Gregory M., 1988, Macroeconomic Theory and Stabilisation Policy, Philip Allan, Great Britain. Sundararajan, V., Dattels, 5. dan Blommesntein, H., 1997, Public Debt and Monetary Management, Washington D.C. Taylor, J.B, 1980, Aggregate Dynamics and Staggered Contracts, Journal of Political Economy, 88:1-22. Taylor, J.B, 1993, Discretion versus Policy Rules in Practice. CarnegieRochester Conference Series Public Policy, 39: 195-214. Taylor, J.B, 2000, The Policy Rule Mix: A Macroeconomic Policy Evaluation, in Calvo, G., Obstfeld, M. dan Donbusch, R (eds) . Robert Mundell Festschrift, Cambridge:505-517. Vane H. R. dan Thompson J.L, 1992, Current Controversies in Macroeconomics: An Intermediate Text, Edward Elgar Publishing Limited, England. Walsh, C.E.,1995, Optimal Contracts for Central Bankers, American Economic Review, No., 85: 150-167. Wickens Michael, 2008, Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach, Princeton University Press. Woodford, M., 1995, Price Level Determinacy Without Control of a Monetary Aggregate, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, No.43, halaman 1–46. Worrel, D., 2000, Monetary and Fiscal Co-ordination in Small Open Economies, IMF Working Paper, WP/00/56, Washington, D.C. Wyplosz, C., 2005, Fiscal Policy: Institutions versus Rules, National Institute Economic Review, No. 191:70-85 Yun, T., 1996, Nominal Price Rigidity, Money Supply Endogeneity and Business Cycles, Journal of Monetary Economics, 37:345-370. 262 PERKEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA Wimboh Santoso dan Dwityapoetra Soeyasa Besar S ektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup tinggi paska krisis. Para pelaku di sektor keuangan menghadapi tantangan baru dalam mengelola modal asing yang masuk sejak krisis global tahun 2008-2009. Data menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadidan memiliki daya tahan yang memadai dalam menghadapi potensi tekanan. Namun demikian, semakin meningkatnya kepemilikan asing dalam surat-surat berharga jangka pendek, perlu diwaspadai adanya potensi pembalikan dana karena sentimen negatif. Dana-dana asing yang masuk tersebut harus disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Dana yang berjangka pendek harus dikelola dengan baik sehingga potensi krisis karena pembalikan dana jangka pendek tersebut dapat diminimalisir. Selain itu rambu dan standar kehati-hatian yang membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh pelaku di sektor keuangan perlu dipantau dengan seksama. 1. Latar Belakang Sektor keuangan Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat paska krisis. Berbagai macam inovasi produk sudah ditawarkan kepada pemodal, infrastruktur pendukung juga telah disiapkan untuk melancarkan transaksi keuangan untuk mendorong fungsi intermediasi dan investasi di sektor keuangan. 263 Sejak pertengahan 2009, sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan pengelolaan arus modal asing yang masuk. Sebagian modal yang berjangka pendek memiliki risiko pasar yang tinggi dan pembalikan yang cepat apabila terdapat sentimen negatif. Risiko tersebut yang harus dihindari agar sektor keuangan Indonesia dapat tumbuh sehat dan menjalankan fungsi intermediasi dengan lancar. Oleh karena itu dalam paper ini, yang disiapkan untuk ISEI, kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya terkait dengan perkembangan sektor keuangan dan daya tahannya dalam menghadapi potensi pembalikan modal asing tersebut. Kontribusi yang diharapkan adalah: (1) memberikan overview mengenai perkembangan sektor keuangan paska krisis dan khususnya kinerja sektor keuangan yang difokuskan pada periode terakhir yaitu Semester 1 2011 dan (2) membahas mengenai potensi risiko dalam sektor keuangan tersebut. Organisasi paper ini adalah sebagai berikut: bagian 1 mengantarkan dengan latar belakang penulisan paper ini. Bagian 2 akan menyampaikan mengenai perkembangan sektor keuangan paska krisis. Bagian 3 membahas perkembangan lembaga keuangan yang terdiri dari bank dan perusahaan pembiayaan. Dilanjutkan dengan bagian 4 yang akan menjelaskan mengenai pasar keuangan yang terdiri dari pasar SUN, pasar obligasi korporasi, pasar saham dan pasar reksadana. Akhirnya adalah kesimpulan. 2. Perkembangan Sektor Keuangan Industri perbankan masih memiliki pangsa terbesar dalam sistem keuangan Indonesia, dilihatdari total asset yang berhasildihimpun. Dengan pangsa sekitar 78,2% dari total asset lembagakeuangan, industriperbankan yang terdiridari Bank Umumdan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih dominan dalam sistem keuangan Indonesia. Peranan lembaga keuangan lain yang cukup menonjol adalah pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransidan Dana Pensiun. 264 Dari sisi jumlah lembaga, peranan industri perbankan juga cukup dominan, khususnya jumlah BPR yang cukup besar. Sementara jumlah Bank Umum relatif sedikit dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan maupun Asuransi. Dengan jumlah yang relatif sedikit namun harus mengelola asset yang besar, pengelolaan Bank Umum terus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Selama semester I 2011, total asset Bank Umum tumbuh 6,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan asset pada periode yang sama tahun 2010 yang hanya sebesar 5,7%. Sementara itu, ketahanan sektor keuangan selama semester I 2011 terjaga dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari Financial Stability Index (FSI) yang turun dari 1,75 (Desember 2010) menjadi 1,65 (Juni 2011), FSI Juni tersebut berada diatas proyeksi sebesar 1,60. Penurunan FSI ini disebabkan oleh relatif terjaganya ketahanan perbankan dan turunnya volatilitas bursa domestik yang didukung oleh solidnya perekonomian domestik dan terkendalinya inflasi. Bayang – bayang ancaman dampak tidak langsung krisis ekonomi Eropa-Amerika menyebabkan FSI Juni berada diatas proyeksi. 265 3. Lembaga keuangan a. Bank i. Sumber Pendanaan Pendanaan bank masih bergantung dari penghimpunan dana masyarakat (DPK). Pangsa DPK sebagai sumber dana bank turun tipis menjadi 87,99% dari semester II 2010 sebesar 91,93%. Sedangkan sumber dana lainnya seperti antar bank hanya menyumbang 5,84% (turun sedikit 6,00%). Pinjaman dan SSB memiliki pangsa yang sangat kecil, masing-masing hanya sebesar 1,17% dan 0,91%. 266 DPK perbankan meningkat hingga Rp99,19 triliun atau 4,24%. Kenaikan DPK ini kurang dari setengah dari kenaikan DPK sebelumnya yang sebesar Rp 242,79 triliun atau 11,58%. Berdasarkan golongan pemilik, terjadi penurunan DPK swastaperseorangan sebesar 0,63%. Pada semester sebelumnya angka ini justru mengalami peningkatan hingga 15,59%. Peningkatan DPK terutama disebabkan oleh kenaikan pada golongan Pemerintah Daerah dan Swasta Perseorangan, masing-masing sebesar 120,67% dan 49,94%. 267 Sesuai dengan trend pada tahun-tahun sebelumnya, kenaikan DPK pada semester pertama lebih rendah daripada semester kedua. Berdasarkan komponen, peningkatan DPK tertinggi adalah dalam bentuk giro dan deposito, yang masing-masing meningkat sebesar 5,99% dan 4,70%. Pada semester sebelumnya, peningkatan DPK tertinggi terjadi pada komponen tabungan dan deposito, masingmasing sebesar 20,03% dan 11,08%. Peningkatan giro tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perekonomian di Indonesia, walaupun terjadi volatilitas perekonomian global. Sementara itu, berdasarkan valuta, pertumbuhan DPK disumbang seluruhnya oleh DPK Rupiah, sementara DPK valas justru mengalami penurunan. Selama periode laporan, DPK rupiah telah bertambah sebesar Rp102,45 triliun, sedangkan DPK valas mengalami penurunan sebesar Rp 3,26 triliun. 268 Risiko Likuiditas Di tengah masih terdapatnya tekanan di pasar keuangan global, likuiditas perbankan berlanjut meningkat selama semester I 2011. Per Juni 2011, total alat likuid perbankan naik hanya sebesar 3,49% (ytd) mencapai Rp897,42 T. Kenaikan alat likuid bersumber dari peningkatan primary reserves bank yang terdiri dari Kas dan giro di BI yaitu sebesar 21,97% yang terutama digunakan untuk memenuhi peningkatan kewajiban GWMLDR (per Maret 2011), GWM valas (5% per Maret 2011 dan 8% per Juni 2011). Sementara itu, selama semester I 2011, secondary dan tertiery reserves perbankan turun masing-masing sebesar 3,15% dan 2,21%. Turunnya alat likuid berupa secondary reserves perbankan terutama dikarenakan cukup besarnya SBI yang jatuh tempo, sementara tenor SBI yang semakin diperpanjang (menjadi 9 bulan) berdampak terjadinya shifting penempatan likuiditas perbankan dari SBI kepada penempatan pada BI lainnya yaitu term deposits dan FASBI. Adapun jangka waktu term deposits yang juga relatif panjang (rata-rata tenor diatas 6 bulan) berdampak terbatasnya peningkatan penempatan pada BI lainnya yaitu naik sebesar 1,75% selama semester I 2011. 269 Kecukupan alat likuid perbankan dalam mengantisipasi terjadinya penarikan DPK masih dalam level yang memadai (rasio AL terhadap DPK >100%). Rasio AL/DPK pada semester I 2011 turun dari 37,08% (Desember 2010) menjadi 36,8% (Juni 2011) dan tidak terdapat individual bank yang berpotensi mengalami kesulitas likuiditas dengan skenario penurunan DPK sebesar 5% (berdasarkan kondisi pada saat krisis 2008, dimana ratarata penarikan DPK mencapai 5%). Sementara itu, kecukupan likuiditas individual bank dalam mengcover kebutuhan penarikan non-core depositnya1 juga masih lebih baik. Masih terdapat lebih banyak bank dengan rasio alat likuid (AL) terhadap non-core deposit (NCD) diatas 100% dan tidak terdapat bank yang rasio AL/NCDnya <50%. ii. Penyaluran Kredit Peningkatan peran intermediasi perbankan masih menjadi salah satu agenda utama kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2011. Baik dalam Paket Kebijakan Bank Indonesia Desember 2010 maupun pada acara pertemuan tahunan perbankan pada awal tahun 2011 ditegaskan perlunya penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dengan memperkokoh stabilitas makroekonomi dan meningkatkan intermediasi dan ketahanan perbankan. Salah satu pesan penting dari kebijakan tersebut, khususnya yang terkait dengan intermediasi perbankan, adalah mengenai masih tetap dipandang perlunya peningkatan intermediasi perbankan khususnya melalui penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan utama bagi pembangunan ekonomi, khususnya untuk membiayai sektor riil. Namun penyaluran kredit yang dilakukan perbankan harus dilakukan dengan tetap berada dalam koridor rambu-rambu prudensial yang telah ditetapkan. Hal ini penting 1 Non-Core Deposit (NCD) merupakan 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito <3 bulan 270 agar penyaluran kredit tidak sampai menimbulkan permasalahan bagi perbankan di kemudian hari yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu penyaluran kredit perbankan harus dilakukan secara hati-hati, selektif dan lebih utama untuk sektor-sektor usaha yang produktif disertai dengan pengelolaan risk management yang baik. Sebagai hasil dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti penerapan ketentuan GWM LDR maupun upaya mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkreditan, perkembangan kredit perbankan pada paruh pertama 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kredit tumbuh 10,5% (ytd) selama semester I 2011 atau tumbuh 23,0% (yoy). Pertumbuhan kredit selama semester I 2011 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada semester I 2010 sebesar 10,3%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan semester II 2010. Percepatan pertumbuhan kredit pada semester I 2011 tersebut tidak terlepas dari semakin kondusifnya kondisi perekonomian yang memungkinkan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya terutama ke sektor-sektor yang produktif. 271 Cukup tingginya pertumbuhan kredit pada semester I 2011 terutama didorong oleh pertumbuhan kredit valas. Selama semester I 2011 kredit valas tumbuh 13,6%, jauh melampaui pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8%. Pesatnya pertumbuhan kredit valas tersebut sudah berlangsung sejak semester II 2010, yang tampaknya tidak terlepas dari perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat. Dengan demikian perbankan harus berhati-hati terhadap risiko pelemahan rupiah yang dapat menyebabkan debitur kesulitan membayar utangnya dan akhirnya menyebabkan kredit bermasalah. Sumber pembiayaan kredit valas selama semester I 2011 berasal dari pencairan penempatan dana antar bank valas yang sifatnya cenedrung jangka pendek, sementara DPK valas justru mengalami pertumbuhan yang negatif. Masih tidak stabilnya kondisi perekonomian global dan relatif tingginya suku bunga di dalam negeri dibandingkan di luar negeri tampaknya berpengaruh pada 272 perilaku perbankan yang memilih untuk menempatkan dana valas untuk kredit di dalam negeri. Oleh karena itu perbankan juga harus berhati-hati terkait dengan sumber pendanaan kredit valas tersebut, karena jika terjadi mismatch berpotensi menimbulkan kerugian tambahan dari selisih nilai tukar. Seperti juga pada semester sebelumnya, peranan kredit ke sektor produktif cukup dominan selama semester I 2011. Perbedaan hanya pada jenis kreditnya. Apabila selama semester II 2010 kredit modal kerja mendominasi penyaluran kredit perbankan, selama semester I 2011 peranan kredit investasi, yang lebih berjangka panjang, semakin dominan dan tumbuh 16,8% (ytd) atau 20,8% yoy. Dengan meningkatnya kredit investasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada sektor riil dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, perbankan harus mewaspadai risiko kredit investasi karena jangka waktunya yang lebih panjang, terutama dikaitkan dengan sumber dana perbankan yang mayoritas masih berjangka waktu pendek. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan risiko mismatch pada perbankan. Sementara itu, dilihat berdasarkan sektornya, hampir semua sektor produktif memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010, kecuali untuk sektor Pertambangan. 273 Pertumbuhan kredit properti yang sempat terpuruk pada tahun 2009, kembali menunjukkan perbaikan sejak pertengahan tahun 2010. Selama semester I 2011 kredit properti tumbuh 10,1% atau 17,8% (yoy). Pertumbuhan selama semester I 2011 tersebut lebih baik dibandingkan dengan dua semester sebelumnya, terutama didorong oleh pertumbuhan kredit properti residensial (KPR) yang tumbuh 11,8%. Dengan kebutuhan perumahan penduduk yang masih cukup besar, kredit properti khususnya untuk rumah tinggal (KPR) diperkirakan berpeluang untuk tetap tumbuh. Pangsa kredit properti terhadap total kredit perbankan saat ini masih relatif tidak terlalu besar, yaitu sekitar 13,2% terhadap total kredit. Risiko Kredit Risiko kredit perbankan selama semester I 2011 sedikit meningkat bila dibandingkan dengan semester II 2010, namun masih terkendali. Pada akhir semester I 2011, rasio NPL gross perbankan mencapai 2,7%, sedikit meningkat dibandingkan posisi Desember 2010 sebesar 2,6%. Selama semester I 2011 terjadi peningkatan jumlah NPL sebesar Rp8,2 T atau sekitar 4,4% dari total peningkatan kredit perbankan pada periode yang sama. Sejalan dengan cukup tingginya pertumbuhan kre274 dit perbankan maka rasio NPL gross hanya naik tipis. Untuk mengantisipasi potensi peningkatan tekanan risiko kredit perbankan meningkatkan pencadangan kerugian kredit sebesar Rp4,2 T atau meningkat 6,8% dari akhir tahun 2010. Dengan cukup tingginya pertumbuhan kredit valas pada semester I 2011, perbankan menghadapi potensi peningkatan risiko kredit valas. Secara historis, rasio NPL kredit valas pernah mencapai diatas 30% pada tahun 2000 sebagai dampak krisis 1997/1998 dan jauh diatas rasio NPL kredit rupiah. Namun, belakangan kinerja kredit valas menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rasio NPL kredit valas sejak Januari 2011 telah berada dibawah rasio NPL kredit rupiah dan per Juni 2011 telah mencapai 2,2% sementara rasio NPL kredit rupiah sebesar 2,8%. Penurunan rasio NPL kredit valas tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah kredit bermasalah yang selalu terjadi beberapa periode terakhir. Selama semester I 2011, jumlah kredit bermasalah kredit valas turun 10%. Dengan demikian, potensi peningkatan risiko 275 kredit yang berasal dari peningkatan kredit valas tampaknya masih dapat dikendalikan oleh bank. Tekanan risiko kredit saat ini tampaknya lebih pada kredit rupiah, yang selama semester I 2011 telah mengalami peningkatan jumlah kredit bermasalah sebesar 23,8%. Bila dilihat dari jenis kreditnya, peningkatan jumlah kredit bermasalah selama semester I 2011 terjadi pada semua jenis kredit, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit Konsumsi. Peningkatan jumlah kredit bermasalah untuk kredit konsumsi tersebut antara lain berasal dari kredit konsumsi untuk Perumahan, kredit multiguna dan kredit konsumsi lainnya. Meskipun pertumbuhan jumlah kredit bermasalahnya adalah yang tertinggi, rasio NPL gross kredit Konsumsi adalah yang terendah dibandingkan jenis kredit lainnya yaitu sebesar 1,9%. 276 Sejalan dengan meningkatnya minat perbankan untuk menyalurkan kredit Investasi, harus disertai juga dengan tetap dijaganya rambu-rambu prudensial terkait prosedur penyaluran kredit tersebut serta kemampuan bank dalam mengelola risikonya. Dengan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan jenis kredit lainnya, kredit Investasi memiliki risiko kredit yang cukup tinggi. Data historis menunjukkan bahwa kredit Investasi memiliki rasio NPL gross lebih tinggi dibandingkan kredit jenis lainnya sejak tahun 2000. Baru setelah memasuki tahun 2009 rasio NPLnya berada dibawah Kredit Modal Kerja. Selama semester I 2011, jumlah nominal kredit bermasalah Kredit Investasi tumbuh 19,1% sehingga rasio NPL grossnya menjadi 2,5%, sedikit meningkat dibandingkan posisi akhir tahun 2010 sebesar 2,4%. Apabila penyalurannya tetap diikuti dengan prinsip kehati-hatian, risiko kredit Investasi ke depan diperkirakan tetap dapat terkendali. 277 Secara sektoral, beberapa sektor mengalami peningkatan jumlah kredit bermasalah selama semester I 2011 seperti Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Konstruksi dan Pengangkutan Komunikasi.Dari sektor-sektor tersebut, sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami peningkatan kredit bermasalah dalam tiga semester terakhir. Sementara itu, risiko penyaluran kredit properti juga masih terkendali. Walaupun rasionya masih sedikit diatas rasio NPL total kredit (per Juni 2011 sebesar 3,0%), namun dengan kecenderungan yang terus menurun. Kenaikan jumlah kredit bermasalah kredit properti selama semester I 2011 terutama bersumber dari kredit untuk KPR. Namun rasio kredit KPR relatif masih cukup rendah yaitu 2,6% per Juni 2011 sehingga peningkatan jumlah kredit bermasalah tampaknya masih dapat dimanage dengan baik oleh bank. iii. Rentabilitas Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, selama semester 1 2011kinerja profitabilitas industri perbankan menunjukkan peningkatan. Perbankan membukukan laba bersih sebesar Rp37,10 T. Laba tersebut lebih tinggi dari semester 1 2010 dan telah mencapai 64,74% dari laba bersih tahun 2010. Kenaikan laba tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya 278 pertumbuhan kredit baik secara ytd (10,47%) maupun yoy (22,96%) pada akhir periode laporan. Tingginya laba tersebut tercermin dari cukup tingginya ROA perbankan yakni sebesar 3,07% per Juni 2011. Jika dilihat per kelompok bank (data Juni 2010 dibandingkan Juni 2011), hanya kelompok bank Persero dan Swasta yang mengalami kenaikan laba bersih (tertinggi pada kelompok bank Persero bahkan telah mencapai 72,99% dari laba bersih tahun 2010). Sedangkan 3 kelompok bank lainnya (BPD, Campuran dan KCBA) sedikit menurun. Kenaikan laba bersih yang cukup tinggi pada kelompok bank Persero dan Swasta antara lain disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan kredit. Sampai dengan akhir semester 1 2011, komposisi laba perbankan masih didominasi oleh laba operasional. Pada Juni 2011, laba operasional perbankan tercatat sebesar Rp26,08 T atau 56% dari total laba. Namun demikian, pangsa laba operasional terhadap total laba perbankan menunjukkan trend yang menurun. Pangsa laba operasional yang cukup dominan tersebut bersumber dari pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) yang meningkat. Rata-rata NII bulanan perbankan selama semester 1 2011 tercatat sebesar Rp13,93 T, lebih tinggi dari semester 1 2010 (Rp12,18 T) dan semester 2 2010 (Rp12,79 T). Oleh 279 karena itu, perkembangan tersebut mencerminkan perbankan dapat melakukan efisiensi dalam hal ini menekan beban bunga, sedangkan di sisi lain dapat meningkatkan pendapatan bunga. Sementara itu, dari sisi sumber pendapatan bunga, pendapatan bunga kredit masih merupakan pangsa terbesar yang pangsanya mencapai 80,95% (per Juni 2011) dari total pendapatan bunga. Namun demikian pangsa tersebut cenderung menurun jika dibandingkan Juni 2010 (81,06%) dan Desember 2010 (81,03%). Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi merupakan penyebab masih dominannya pendapatan bunga kredit. Sementara itu, spread suku bunga yang cenderung menyempit menyebabkan pangsa pendapatan bunga kredit terhadap total pendapatan bunga mengalami penurunan. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan, perbankan lebih mengutamakan peningkatan volume kredit dibandingkan melebarkan spread suku bunga. Spread yang menyempit tersebut juga menyebabkan Net Interest Margin (NIM) perbankan mengalami penurunan sebesar 1 bp yakni dari 5,80% (Juni 2010) menjadi 5,79% (Juni 2011). 280 Indikator profitabilitas lainnya yaitu rasio Return on Asset (ROA) juga menunjukkan peningkatan. ROA meningkat dari 3,0% (semester 1 2010) dan 2,86% (akhir 2010) menjadi 3,07% pada akhir semester laporan. Peningkatan rasio ROA tersebut antara lain didorong oleh membaiknya kinerja efisiensi perbankan yang tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO pada semester 1 2011 tercatat sebesar 85,92% atau lebih rendah dari semester 1 2010 (90,47%) dan akhir tahun 2010 (86,14%). iv. Permodalan Selama semester 1 2011, industri perbankan dapat menjaga permodalan dengan baik. Rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat sebesar 17,53% atau lebih tinggi dari rata-rata CAR selama semester 2 2010 (16,79%), namun lebih rendah dari semester 1 2010 (18,31%). Kenaikan rata-rata CAR pada semester 1 2011 dibandingkan semester sebelumnya disebabkan pertumbuhan modal lebih tinggi dari kenaikan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rata-rata modal pada semester 1 2011 naik sebesar Rp68,44 T atau 22,38% dibandingkan rata-rata modal pada semester 2 2010. Sementara itu, rata-rata ATMR pada periode yang sama meningkat Rp314,24 T atau 17,26% dibandingkan semester sebelumnya. 281 Berdasarkan kelompok bank, pada Juni 2011 CAR tertinggi terdapat pada kelompok KCBA (25,29%) diikuti Campuran (22,0%), sedangkan yang terendah pada kelompok BPD (14,24%) dan Swasta (15,66%). Adapun CAR kelompok bank Persero tercatat sebesar 16,43%. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang cukup tinggi pada kelompok bank Swasta, BPD dan Persero, sedangkan pertumbuhan kredit kelompok bank Campuran dan KCBA relatif rendah. Dari sisi trend, hanya CAR kelompok bank Persero yang trend-nya meningkat, sedangkan 4 kelompok bank yang lain cenderung menurun, terutama pada kelompok KCBA yang mengalami penurunan cukup tinggi. 282 v. Penyaluran Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Kredit MKM masih merupakan penyumbang terbesar terhadap total kredit perbankan. Pada Juni 2011, pangsa kredit MKM tercatat sebesar 53,06%, lebih tinggi dari Juni 2010 (52,68%) dan Desember 2011 (52,48%). Pangsa yang dominan tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit MKM yang lebih tinggi dari kredit non MKM. Pada akhir semester laporan, kredit MKM tumbuh 11,69% (ytd) dan 23,85% (yoy), sedangkan kredit non MKM tumbuh lebih rendah yakni 9,12% (ytd) dan 21,96% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan kredit MKM pada Juni 2011 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Juni 2010 baik secara ytd maupun yoy. 283 Walaupun pertumbuhan kredit MKM tinggi, namun rasio NPL gross tetap terjaga pada level yang rendah yaitu sebesar 2,87% per Juni 2011. NPL gross tersebut lebih tinggi dari Juni 2010 (2,82%) dan Desember 2010 (2,60%). Kondisi ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi perbankan dalam meningkatkan penyaluran kredit MKM, selain semakin banyak bank yang juga masuk ke sektor MKM. Data kredit MKM tidak termasuk kartu kredit dan BPR/BPRS, namun sudah termasuk Bank Umum Syariah (BUS). 284 b. Perusahaan Pembiayaan Positifnya pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2010 sampai 2011yang didukung dengan stabilnya suku bunga dan inflasi mampu meningkatkan pasar pembiayaan PP pada semester 1 2011. Total asset PP naik sebesar 12,67% atau 28,76% (yoy) menjadi Rp 259,55 triliun. Sumber pembiayaan kegiatan pembiayaan PP yang naik sebesar 14,00% atau 30,17% (yoy) menjadi Rp 212,44 triliun terutama didukung oleh kenaikan modal sebesar 2,63% atau naik 285 9,83% (yoy) sementara,pendanaanPPyang bersumber dari pinjaman dan obligasi naik hanya sebesar17,40atau naik 44,44% (yoy).Kenaikan pembiayaan PP terutama bersumber dari kegiatan pembiayaan konsumen yang pangsanya terhadap total pembiayaan naik menjadi 71,10% (Desember 2010 sebesar 69,77%) atau Rp 151,04 triliun (Juni 2011). Perkembangan tersebut berdampak semakin meningatnya risiko konsentrasi PP. Sumber pendanaan PP yang masih didominasi oleh perbankan relatif berkurang pertumbuhannya seiring meningkatnya aktifitas penerbitan obligasi. Relatif stabilnya suku bunga domestik selama semester I 2011 yang didukung semakin baiknya outlook ekonomi mendorong penerbitan obligasi PP sehingga naik sebesar 52,38% menjadi Rp 28,02 triliun. Pendanaan yang bersumber dari pinjaman perbankan dalam negeri naik hanya sebesar 13,94% menjadi Rp 96,94 triliun sementara, pinjaman perbankan luar negeri naik sebesar 11,61% menjadi Rp 67,22 triliun. Berkurangnya ketergantungan PP terhadap sumber dana perbankan sedikit mengurangi risiko eksposure perbankan. 286 Kinerja PP pada semester 1 2011sedikit melambat sebagaimana terindikasi pada penurunan profit sebelum pajak yang berkontribusi berkurangnya rasio return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) dibandingkan posisi Desember 2010. Adapun dari segi effisiensi, perusahaan pembiayaan tetap mampu mempertahankan efisiensi usaha sebagaimana terindikasi pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang stabil pada level 0,79% seiring berkurangnya sumber pendanaan berupa pinjaman perbankan. Pada semester 1 2011, ditengah cukup pesatnya pertumbuhan pembiayaan PP, terjadi kenaikan nominal NPL PP sebesar 7,10% menjadi sebesar Rp 2,85 triliun (pada sem II 2010 terjadi penurunan NPL sebesar 8,41%). Pada akhir semester 1 2011, NPL PP turun dari 1,37% (Desember 2010) menjadi 1,29% (Juni 2011). Turunnya 287 NPL PP terutama berasal dari turunnya nominal NPL pada kegiatan pembiayaan sewa guna usaha dan kartu kredit. Sementara, penurunan NPL terjadi pada semua kegiatan PP, yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. 4. Pasar Keuangan a. Pasar SUN Berdasarkan indeks IDMA, selama semester I harga SUNturunsekitar 4,11% menjadi101,69.Melemahnya harga SUN dikarenakan memanasnya isu tingginya inflasi di negara emerging markets pada awal semester I akibat economic overheating dan tingginya harga minyak. Investor menggunakan isu ini untuk melakukan aksi profit taking. IDMA pada 2010 (yoy) telah menguat sebesar 12,38%.Pada semester I-2011, harga rata-rata SUN berada pada kisaran 102,26 (21/1) sampai dengan 115,90 (4/1).Sementara itu, berdasarkan tenor, harga rata-rata bulanan SUN tenor pendek (<5tahun) dan menengah (5 s.d. 7 tahun) turun paling signifikan, masing-masing sebesar 228 bps (turun2,08%) dan 48 bps (turun0,42%). Sementara, SUN tenor panjang (> 7 tahun) naik sebesar 245 bps (naik2,12%). Tingginya ekspektasi inflasi pada awal tahun menyebabkan naiknya potensi risiko SUN, namun berangsur stabil setelah BI Rate dinaikkan untuk meredam ekspektasi inflasi tersebut. 288 Pada semester II-2011, khususnya pada bulan Agustus 2011 harga rata-rata SUN mengalami peningkatan sekitar 1,14% menjadi 108,01. Namun berdasarkan tenor, peningkatan terjadi untuk tenor menengah (5 s.d. 7 tahun) dan panjang (> 7 tahun), masing-masingsebesar 177 bps (naik1,56%) dan 913 bps (naik 7,8%). Sedangkan untuk tenor pendek (<5 tahun) turun sebesar 238,62 (turun 2,18%). Selama 2011, posisi obligasi pemerintah naik sebesar 7,77% menjadi Rp 691,03 triliun, terutama didukung oleh meningkatnya kepemilikan SBN oleh investor asing sebesar Rp 39,69 triliun (portofolio SBN asing mencapai 34,00% dari total outstanding SBN). Investor asing cenderung melakukan pembelian SUN yang harganya murah, sementara perbankan yang dominan SUN terindikasi mengurangi penanaman (portofolio SUN perbankan turun dari 34,23% menjadi 32,78%). Periode awal semester II-2011 sampai posisi Agustus 2011, obligasi pemerintah naik sebesar 9,79% menjadi Rp 703,98 triliun, dan kepemilikan SBN oleh investor asing sebesar Rp 52,08 triliun (portofolio SBN asing mencapai 35,00% dari total outstanding SBN). Dalam semester kedua tahun 2011 kempemilikan SUN masih akan didominasi oleh asing. Peningkatan yang terjadi pada bulan agustus akan mengindikasikan bahwa dalam kuartal kedua masih akan terjadi peningkatan kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah. 289 b. Pasar Obligasi Korporasi Selama semester pertama tahun 2011,pertumbuhan pembiayaan melalui pasar saham meningkat sebesar 7,21% menjadi Rp 531,1 triliun pada semester 1 2011 (sem II 2010 sebesar 13,12%). Secara yoy, nilai emisi saham naik sebesar 21,37%(tahun lalu naik sebesar 18%). Sementara itu, melambatnya penguatan indeks saham selama tahun 2011 berdampak sedikit melambatnya peningkatankapitalisasi pasar sebesar 45,69% (44,37% posisi Agustus) secara yoy(tahun lalu naik sebesar 60,8%). Melambatnya pertumbuhan kapitalisasi pasar saham terutama bersumber dari melambatnya kenaikan pada semester 1 2011 yang hanya sebesar sebesar 7,73% (6,75% posisi Agustus). (Sem II 2010 tumbuh 35,24%). Sementara itu, jumlah perusahaan yang melakukan emisi saham bertambah 14 perusahaanmenjadi 535 perusahaan pada semester 1 2011. 290 Pembiayaan korporasi melalui penerbitan obligasi korporasi selama semester 1 2011 meningkat didukung oleh stabilnya suku bunga dan inflasi. Nilai emisi obligasi di pasar modal pada semester 1 2011 naik sekitar 12,56% menjadi Rp 242,14 miliar (sem II 2010 naik sekitar 14,81%).Perusahaan emiten obligasi bertambah 5 perusahaan menjadi 194 perusahaan. Rendahnya suku bunga domestik dan baiknya outlook ekonomi mampu memelihara likuiditas pasar obligasi korporasi. Selama semester 1 2011, 24 emiten korporasi telah melakukan penerbitan obligasi korporasi yang secara keseluruhan mencapai sebesar Rp 27,01 triliun (sepanjang tahun 2010 sebesar Rp 36,60 triliun oleh 26 emiten). Dalam rangka refinancing, dari 24 emiten yang melakukan emisi obligasi, 8 emiten diantaranya juga menerbitkan obligasi pada tahun lalu. Selama 2011, terdapat 15 PP yang melakukan emisi obilgasi (tahun 2010 terdapat 7 PP). Sedangkan selama sem II 2011 nanti akan ada 15 obligasi yang mengalami jatuh tempo dengan nilai total obligasi jatuh tempo sebesar Rp 6,34 triliun. 291 c. Pasar Saham Selama semester I 2011, IHSG berlanjut bullish didukung stabilnya pertumbuhan ekonomi global, domestik, danperforma memuaskan dari emiten bursa. Sentimen utama penguatan bursa global pada semester I 2011 masih dipicu oleh The Fed yang memperkenalkan program quantitative easing tahap II senilai US$600 miliar dan dipertahankannya suku bunga 292 rendah oleh bank sentral beberapa negara maju seperti AS, Eropa, Inggris, dan Jepang. Kedua sentimen ini berhasil menciptakan likuiditas dipasar yang memicu terus tumbuhnya permintaan akan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi global paska krisis 2008. Tumbuhnya perekonomian ini tercermin pada membaiknya laporan perekonomian seperti naiknya kegiatan manufaktur dan GDP di AS, China, Eropa, dan emerging markets sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia. Positifnya laju perekonomian juga terlihat dari naiknya keuntungan emiten-emiten di bursa global pada laporan kuartalan mereka. Laju penguatan bursa global tertahan pada akhir semester I 2011 setelah beberapa bank sentral menaikkan suku bunga acuan mereka untuk mencegah overheating dalam perekonomian. Sentimen negatif juga datang dari tingginya harga minyak akibat gejolak di Mesir dan Libya, gempa dan tsunami yang memporakporandakan perekonomian Jepang, kekhawatiran pasar akan default obligasi Yunani yang diperkirakan akan menyebar ke negara lain dan berhentinya program quantitative easing II pada 30 Juni. Sentimen-sentimen ini menimbulkan ekspektasi akan melandainya pertumbuhan ekonomi dunia karena mengeringnya likuditas yang berujung pada melemahnya permintaan. Selama semester 1 2011 indeks tumbuh 5,00% ke level 3.888,57 (lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sem II 2010 yang sebesar 27,11%). Membaiknya perekonomian global dan domestik memicu turunnya persepsi resiko sehingga menyebabkan masih besarnya inflow dana asing. Peringkat rating credit Indonesia yang satu tingkat dibawah investement grade juga menjadi salah satu alasan derasnya inflow ke pasar dalam negeri. Laju penguatan indeks tertahan oleh koreksi yang terjadi pada bulan Januari yang mendekati 10% karena isu tingginya ekspektasi inflasi akibat tingginya harga minyak yang pada saat itu diatas US$110/barel. 293 Solidnya pertumbuhan perekonomian domestik dan performa emiten bursaseiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global menimbulkan ekspektasi akan bertambahnya tingkat permintaan, berimbas rally sahamsaham sektor Aneka Industri (naik 18,11%), Perdagangan (naik 11,77%) dan Keuangan (naik 37,57%) pada semester 1 2011. Menguatnya indeks Keyakinan Konsumen Indonesia dari 103 (Desember 2010) menjadi 109 (Juni 2011), kenaikan annual GDP (yoy) sebesar 6,50%, terus tumbuhnya penjualan mobil dan sepeda motor, naiknya penjualan semen sebesar 15% pada semester I, menguatnya harga barang komoditas dan berkembangnya kegiatan ekspor-impor Indonesia yang secara yoy tumbuh 45,3% dan 48,5%menunjukkan berkembangnya perekonomian Indonesia yang melatarbelakangi penguatan IHSG. Terkendalinya inflasi dan stabilnya BI Rate menjadi sentimen utama penguatan sektor Perbankan, Aneka Industri, dan Perdagangan yang penjualan barang atau jasanya sensitif terhadap pergerakan suku bunga. 294 Volatilitas bursa domestik pada semester I 2011turun dari 23,83 (Desember 2010)menjadi 13,59 (Juni 2011). Membaiknya performa IHSG yang ditopang kuatnya pertumbuhan fundamental perekonomian dan emiten bursa Indonesia menyebabkan turunnya volatilitas bursa. Stimulus fiskal yang terus diberikan oleh Bank Sentral berbagai negara dan tumbuhnya perekonomian dunia cukup mampu menahan volatilitas bursa global. Volatilitas bursa Jepang terpantau melonjak akibat terjadinya gempa dan tsunami pada bulan Maret 2011. 295 Stabilnya BI rate, terkendalinya inflasi, pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 23,4%, dan laju NPL yang dibawah 5% selama 2011 mendukung baiknya perkembangan kinerja perbankan. Selama tahun 2011, harga saham perbankan domestik ditutup mixedsetelah terjadi aksi profit taking meyusul telah tingginya kenaikan indeks sektor finansial pada tahun 2010 (yoy) sebesar 55%. Diantara saham perbankan, saham-saham perbankan yang harganya menguat selama semester I’2011 (yoy) adalah BCA sebesar 28,57%, Mega sebesar 33,02%, Niaga sebesar 60,75%, Permata sebesar 36,13%, BII sebesar 92,98%, Mandiri sebesar 20,00%, Bukopin sebesar 2,99%, Danamon sebesar 11,11%, BNI sebesar 64,89% dan NISP sebesar 1,30%. Sementara itu saham bank yang melemah adalah Panin sebesar 10,78%, dan BRI sebesar 30,11%. Pelemahan bank BRI disebabkan oleh stock split. d. Kepemilikan Asing di SBI, SUN dan Saham Optimisme investor asing menguatyang tercermin dari meningkatnya inflows asing pada asset keuangan rupiah (SBI, SUN dan saham) sebesar Rp 64,00 triliun (pada semester II 2010 sebesar Rp 56,31triliun). Inflows asing terutama bersumber dari kenaikan portofolio SUN asing dan net beli saham asing masing-masing sebesar Rp39,32 triliun dan Rp18,03 triliun, sementarakenaikan portofolio asing di SBIsebesar Rp 6,64 triliun. 296 Pada kuartal II 2011, minat investor pada SBI berkurang setelah keluarnya peraturan 6 bulan holding period yang membatasi ruang gerak trading investor sehingga memicu aksi switching portofolio dari SBI menjadi SBN dan saham. Adapun porsi kepemilikan asing pada SBI naik dari 27,45% (Desember 2010)menjadi 33,12% (Juni 2011) dan porsi kepemilikan asing pada SBN naik dari 29,93% (Desember 2010) menjadi 33,01% (Juni 2011). Sementara itu, posisi saham asing meningkat dari 32,29% (Desember 2010) menjadi 35,88% (Juni 2011). Inflow terus berlanjut pada awal semester II-2011 sampai dengan bulan Agustus. Kenaikan penanaman asing berjangka pendek berdampak tren menguatnya rupiah namun berpotensi meningkatkan tekanan koreksi apabila terjadi pembalikan dana. e. Pasar Reksadana Jumlah reksa dana pada semester 1 2011 naik, dari 558 pada Desember 2010 menjadi 632 pada Juni 2011. Sementara, kinerja reksadana kembali terindikasi meningkat sebagaimana tampak pada kenaikan NAB selama semester I 2011 yaitu sebesar 5,34% (sem II’10 naik sebesar 21,61%). Berdasarkan jenis reksadana, kenaikan NAB reksadana terutama bersumber dari kenaikan NAB reksadana saham dan Terproteksi yang masing-masing naik sebesar 22,59% (22,66% posisi Agustus) dan 1,87% (1,60% posisi Agustus) menjadi Rp 55,98 triliun (Rp 56,02T posisi Agustus) dan Rp 290 miliar (Rp 42,68T posisi Agustus) dipicu tren menguatnya IHSG. Adapun 297 kinerja reksadana ETF-saham dan ETF-pendapatan tetap yang relatif baru terindikasi naik sebesar 4,79% (11,02% posisi Agustus) dan 5,39% (9,74% posisi Agustus), reksadana index naik signifikan yaitu sebesar 12,23% (17,93% posisi Agustus) meski NAB tetap relatif rendah yaitu sebesar Rp 290 miliar (Rp 210 miliar posisi Agustus) 5. Kesimpulan Sektor keuangan Indonesia berkembang dengan pesat sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan aliran modal asing dalam pasar keuangan. Hal ini terbukti dari peningkatan intermediasi baik lembaga maupun pasar keuangan kepada sektor riil yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, ketahanan pelaku di pasar keuangan khususnya perbankan cukup tinggi. Derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia harus dikelola dengan baik. Inovasi dan pendalaman pasar keuangan perlu dilakukan. Kondisi ini dapat memberikan pengatuh positif kepada Indonesia untuk pengembangan sektor keuangan. Namun demikian, semakin meningkatnya kepemilikan asing dalam surat-surat berharga jangka pendek, perlu diwaspadai karena adanya potensi pembalikan dana apabila ada sentimen negatif. Dana-dana asing yang masuk tersebut harus disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Dana yang berjangka pendek harus ditahan sehingga potensi krisis karena pembalikan dana jangka pendek tersebut dapat diminimalisir. Selain itu rambu dan standar kehati-hatian yang membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh pelaku di sektor keuangan perlu diketatkan dan tata kelola yang baik juga perlu diwujudkan dalam kegiatan operasional di sektor keuangan. Standar-standar yang baik tersebut perlu dievaluasi untuk meyakinkan penerapannya dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Akhirnya, Bank Indonesia sebagai salah satu otoritas makroprudensial yang akan memberikan kontribusi dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan telah mengembangkan kerangka SSK dan menyusun mekanisme koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pencegahan 298 dan penanganan krisis. Hal tersebut ditujukan utk melengkapi berbagai standar dan pedoman yang sudah ada sehingga kepercayaan masyarakat dan pelaku di sektor keuangan tetap terjaga dan akan meningkat. Kegiatan intermediasi yang berjalan dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. 299 300 PENTINGNYA PEMELIHARAAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: RISIKO SISTEMIK DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL Wimboh Santoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Primitiva Febriarti Stabilitas sistem keuangan keuangan wajib dipelihara untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya nyata sedang dilakukan terkait dengan mencari solusi terhadap terjadinya krisis keuangan 2008-2009 dan memperbaiki sistem pengawasan bank secara lebih terfokus. Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah perlunya kerangka kebijakan yang memiliki jangkauan luas untuk memelihara kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan makroprudensial.Kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi risiko keuangan yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, dalam implementasinya kebijakan makroprudensial harus dilengkapi dengan berbagai perangkat yaitu tujuan, cakupan analisis, kewenangan dan piranti serta tata kelolanya.Bank sentral khususnya sebagai lembaga yang memiiliki piranti dan keahlian dituntut untuk berperan. Bank Indonesia perlu diberikan mandat secara eksplisit di bidang stabilitas sistem keuangan. Mandat ini perlu diformalkan dalam undang-undang bank sentral. Tugas terkait stabilitas sistem keuangan yang tercantum dalam UU BI saat ini masih belum cukup memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan di bidang stabilitas sistem 301 keuangan (macroprudential policy). Keterkaitan yang erat antara mandat di bidang stabilitas sistem keuangan dengan undang-undang lainnya seperti RUU Otoritas Jasa Keuangan yang akan segera diterbitkan dan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang diperlukan untuk penanganan krisis hendaknya dapat dijembatani dengan koordinasi yang kuat dan kredibel sehingga tujuan stabilitas sistem keuangan dapat tercapai. 1. Latar belakang Krisis perbankan dewasa ini membuat kita sadar bahwa risiko yang menjadi signifikan pada satu aspek sistem keuangan dapat mempunyai dampak yang luas, mempengaruhi pasar keuangan dan lembaga keuangan sertastabilitas makroekonomi. Namun yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penuntun terjadinya peristiwa tersebut dan dapat berdampak kepada seluruh sistem keuangan? Selain itu juga apakah yang dapat dilakukan untuk menurunkan potensi peristiwa sistemik dan mengurangi dampaknya apabila peristiwa itu terjadi? Dalam paper ini, yang disiapkan untuk ISEI, kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Laporan ini tidak ditujukan untuk menggunakan informasi baru. Telah ada kajian literatur dalam krisis perbankan, nilai tukar dan pasar saham. Kontribusi kami adalah: (1) memberikan overview mengenai krisis sistemik (2) membahas mengenai implementasi yang dilakukan oleh lembaga internasional yang menjadi best practice, dan akhirnya (3) bagaimana pengambil kebijakan publik dapat memberikan respon terhadap risiko yang terjadi karena peristiwa sistemik tersebut. Organisasi paper ini adalah sebagai berikut: setelah latar belakang maka pada bagian 2 akan dibahas mengenai definisi risiko sistemik dan kebijakan makroprudensial. Definisi sistemik digambarkan sebagai suatu titik awal gangguan yang ditransmisikan melalui jaringan yang menghubungkan perusahaan, rumah tangga dan lembaga keuangan. Bagian 3 akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan makroprudensial secara global yang menjadi best practice. Bagian 4implementasi di Bank Indonesia baik 302 terkait dengan kerangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Bagian final adalah kesimpulan. 2. Definisi krisis dan kebijakan makroprudensial a. Risiko sistemik Dalam bagian ini akan dibahas mengenai penyebab masalah sistemik di perbankan. Oleh karena itu dapat ditawarkan definisi risiko sistemik dan menggunakan definisi tersebut untuk risiko sistemik yang timbul khususnya di sektor perbankan. Risiko sistemik berbeda dibandingkan dengan gangguan besar yang berdampak terhadap seluruh lembaga keuangan. Banyak tekanan besar dari sumber yang sama terhadap lembaga keuangan. Namun hal tersebut bukanlah risiko sistemik. Sebagai contoh adanya penurunan pengeluaran aggregat (misalnya karena meningkatknya terms of trade sehingga memberikan tekanan pada ekspor). Penurunan tersebut dapat meningkatkan kegagalan kredit dan menurunkan pendapatan beberapa bank. Namun apabila hal tersebut tidak mempengaruhi solvensi dari bank, penurunan likuiditas perbankan yang menyebabkan kegagalan pasar kredit atau berfungsinya sistem keuangan dan perekonomian maka kondisi tersebut hanya dianggap sebagai tekanan yang memiliki sumber yang sama. Demikian pula, mungkin terjadi masalah sistemik namun hanya memberikan dampak yang kecil dibandingkan dengan krisis perbankan. Oleh karena itu, apabila kita mendefinisikan risiko sistemik sebagai krisis perbankan atau keuangan yang besar saja artinya kita kurang memperhatikan masalah sistemik yang dapat terjadi pada cakupan yang lebih kecil. Hal tersebut menyebabkan perlu memisahkan antara krisis sistemik dan tekanan yang besar yang dapat mempengaruhi lembaga keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya apa yang membedakan risiko sistemik dan tekanan yang sumbernya sama tersebut dan berpotensi sistemik? Kita perlu mendefinisikan tentang risiko sistemik. 303 Risiko sistemik menjadi signifikan apabila gangguan awal yang ditransmisikan melalui jaringan yang menghubungkan antara perusahaan, rumah tangga dan lembaga keuangan mengarah atau menjadi gagal atau merusak jaringan tersebut. Jaringan adalah pasar atau mekanisme lain yang digunakan oleh perusahaan, rumah tangga dan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi ekonomi diantara mereka.Hal ini untuk menjelaskan bahwa ada perbedaan antara risiko sistematik dan risiko sistemik. Risiko sistematik tidak mencerminkan adanya kegagalan atau tidak bekerjanya hubungan antara perusahaan, rumah tangga dan lembaga keuangan. Namun apabila terjadikegagalan atau tidak bekerjanya jaringan tersebut maka risiko sistematik menjadi sistemik (ada unsur penularan dan keterkaitan). Contoh klasik dari risiko sistemik keuangan yang signifikan adalah kasus Herstatt atau risiko sistem pembayaran yang melanda pasar uang di New York pada tahun 1974. Kegagalan sistem tersebut adalah karena fraud dari kantor cabang Herstatt yang menyebabkan jatuhnya sistem pasar uang antar bank New York-CHIPS. Fitur utama kegagalan ini adalah karena ketiadaannya delivery against payment di pasar uang pada saat itu. Fraud tersebut menyebabkan transfer dalam AS$ tidak dapat dilakukan dan menyebabkan kekeringan (tidak berfungsinya) di pasar antar bank (tidak ada yang mau membayar dan menjadi terekspose dengan risiko counterparty) dan tidak ada bank yang bersedia menanggung beban karena terkena dampak pada surat-surat berharga dan setelmen transaksi lainnya. Kondisi ini telah mengancam sistem keuangan AS. Definisi yang kami tawarkan relatif lebih spesifik dibandingkan dengan definisi lain yang pernah dinyatakan dalam paper-paper lain.Asumsi umum yang digunakan adalah bahwa setiap tekanan ekonomi yang menyebabkan tekanan dalam sistem keuangan yang meluas atau terjadinya insolvensi dari lembaga keuangan adalah krisis sistem keuangan. Hasil itu juga dapat masuk dalam definisi yang ditawarkan tersebut. Sebagai contoh, apabila terjadi tekanan yang besar- dari luar dan kejadian yang epidemik maka konsekuensi yang akan terjadi adalah insolvensi yang meluas, dan kegagalan pasar serta mekanisme lain yang mendukung aktivitas perekonomian. 304 Definisi ini akan bermanfaat khususnya apabila terjadi krisis sistemik yang melibatkan sektor keuangan dengan skala yang besar dan insolvensi para pelaku pasar. Dengan membedakan risiko-risiko yang dapat menyebabkan kegagalan berbagai jaringan di perbankan dan jasa-jasa keuangan, kita dapat mengidentifikasi aksi yang spesifik untuk melakukan mitigasi terhadap risiko tertentu. Definisi tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan ‘one size fits all” untuk melakukan analisa dan merespon potensi risiko sistemik. Pada saat ini sedang berkembang analisa jaringan keuangan khususnya menerapkan analisa sistem adaptif yang kompleks yang sering dilakukan dalam biologi dan ilmu alam. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan baru tersebut dapat mengembangkan model-model yang dapat menjawab permasalahan sistem keuangan yang tidak stabil. Selain itu, dalam perkembangannya, lembaga multilateral juga telah memberikan kontribusi terhadap definisi risiko sistemik yang bersumber dari dua dimensi, yaitu: Time: menunjukkan pergerakan siklikal risiko sistemik (procyclicality), dengan contoh beberapa instrumen: countercyclical capital, loan to value ratio, dynamic provision dll Cross-section: mencerminkan distribusi risiko dalam sistem keuangan pada suatu titik waktu, dengan contoh instrumen: systemic capital surcharges, systemic liquidity surcharges dll b. Kebijakan makroprudensial Definisi kebijakan makroprudential masih berkembang dan belum mengarah pada satu kesimpulan akhir.Beberapa lembaga multi lateral dan bank sentral telah mencoba untuk memberikan definisi kebijakan makroprudensial. Secara umum, berbagai definisi sepakat dengan tujuan dilakukannya kebijakan makroprudensial adalah dalam rangka pencegahan terjadinya risiko sistemik dan upaya untuk mengurangi biaya krisis sebagai tujuan akhir. 305 Selain itu, Working Group G30 telah memberikan definisi kebijakan makroprudensial yang mencakup 4 (empat) komponen, yaitu: Respon Kebijakan terhadap Sektor Keuangan secara Menyeluruh Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan respon kebijakan yang tepat bagi sistem keuangan secara keseluruhan dan tidak terkonsentrasi pada suatu institusi secara individu ataupun kebijakan ekonomi tertentu. Meningkatkan Ketahanan Sistem Keuangan dan Membatasi Risiko Sistemik Kebijakan makroprudensial bertujuan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan mengurangi risiko sistemik yang inheren dalam sistem keuangan yang disebabkan oleh keterkaitan (interconnectedness) antar institusi, kerentanan terhadap shock dan kecenderungan institusi keuangan untuk bergerak secara procyclical yang berpotensi meningkatkan volatilitas siklus keuangan. Perangkat Kebijakan Makroprudensial Kebijakan makroprudensial menggunakan berbagai perangkat pengawasan prudensial, baik yang sifatnya berkesinambungan maupun yang digunakan bilamana diperlukan untuk memitigasi kecenderungan procyclical, serta menerapkannya dalam rangka meminimalisasi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dalam menyerap risiko tersebut. Koordinasi Kebijakan Makroprudensial Institusi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan makroprudensial harus melakukan tukar menukar informasi mengenai kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan pemerintah lainnya dengan memperhatikan tanggung jawab utama instansi lain yang terkait. Berbagai institusi internasional dan bank sentral juga memberikan definsi terhadap kebijakan makroprudensial. Diantaranya adalah: 306 IMF: Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. (IMF, Macroprudential Policy: An Organizing Framework, 2011) BIS: Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik (BIS working papers, Macoprudential policy - a literature review, February 2011) Bank of England: Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk memelihara kestabilan intermediasi keuangan (misalnya jasa-jasa pembayaran, intermediasi kredit dan penjaminan atas risiko) terhadap perekonomian (Bank of England (2009), “The Role of Macroprudential Policy”, Bank of England Discussion Paper) Definisi kebijakan makroprudensial menunjukkan bahwa cakupan kebijakan ini cukup luas. Oleh karena itu dalam implementasinya untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudential akan berinteraksi dengan berbagai kebijakan lainnya misalnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan mikroprudensial dan kebijakan lainnya (perlindungan konsumen, tata kelola dll) (lihat Gambar 1). Namun, kebijakan makroprudensial harus menjadi pilihan utama apabila kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan upaya untuk membatasi terjadinya risiko sistemik. Sebagai contoh adalah interaksi kebijakan makroprudensial dengan kebijakan mikroprudensial dan kebijakan moneter. Hal ini karena kedua kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh kepada biaya risiko kepada sistem keuangan dan perekonomian. Semakin besar cadangan yang dibentuk dengan penerapan kebijakan mikroprudensial maka semakin kecil peranan kebijakan makroprudential. Demikian halnya dengan kebijakan moneter. Apabila kecenderungan kebijakan moneter lebih mendukung pada ketidakseimbangan maka peranan kebijakan makroprudensial juga semakin kecil. Oleh karena itu perlu untuk digaris bawahi bahwa kebijakan makroprudential tidak dapat menggantikan kebijakan lain secara umum, 307 khususnya regulasi dan pengawasan mikro prudential dan kebijakan makroekonomi yang dikelola baik. Selain itu, untuk kebijakan mikro dan makro prudensial perlu dibedakan secara konsepsi untuk menghindarkan konflik kepentingan yaitu bahwa kebijakan mikroprudensial ditujukan untuk mengatasi risiko idiosyncratic dan perlindungan nasabah sedangkan kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mengatasi risiko sistemik. Gambar 1. Kerangka Kebijakan Stabilitas Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial Sumber: Brockmeijer, et.al, (2011) 1. Best practices dan implementasi di negara lain Dalam memitigasi meluasnya dampak krisis, diatasi dengan biaya bail out dengan menggunakan dana public yang cukup besar. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia pada krisis 1997/1998, AS dan Inggris juga mengeluarkan biaya bail out yang sangat besar. Pada krisis global 2008, AS 308 dengan persetujuan Konggres mengucurkan paket dana talangan hingga mencapai USD700 milyar untuk menyelamatkan tidak saja perbankan, tetapi juga capital market, perusahaan asuransi, mutual fund termasuk korporasi. Hal ini menjadi tonggak sejarah bank sental modern dimana bank sental tidak saja membantu bank tapi juga non bank. Besarnya nominal dana talangan ini menyebabkan membesarnya defisit anggaran AS hingga mencapai 7%. Sementara itu, pada awal September 2007, Bank of England (BoE) juga melakukan penyelamatan terhadap Northern Rock yang notabene bukan bank kategori besar. BoE mengeluarkan biaya penyelamatan sebesar GBP3 milyar, untuk menghindari bank run terhadap bank tersebut sekaligus mengurangi dampak contagion kepada bank lain. Pengalaman krisis tersebut menunjukkan bahwa bank sentral memiliki peran yang krusial dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.Peranan ini bukanlah peran yang baru, namun eksistensinya semakin diperkuat dengan adanya pengalaman krisis keuangan global dan perkembangan isu di sektor keuangan.Pengalaman krisis menunjukkan bahwa bank sentral dituntut untuk melangkah lebih jauh dari konsep kebijakan moneter dan terlibat dalam upaya memelihara SSK. Pada prakteknya peran stabilitas sistem keuangan di bank sentral kurang memiliki kejelasan, landasan konsep dan definisi yang jelas.Berbeda dengan tujuan mencapai stabilitas harga, di beberapa negara peran menjaga SSK tidak dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang bank sentral. Hal ini menyebabkan pelaksanaan peran bank sentral sering didasarkan pada interpretasi undang-undang .Dengan tidak adanya mandat secara eksplisit, bank sentral tidak memiliki akuntabilitas yang jelas dalam memelihara SSK.Meskipun di beberapa Negara komitmen bersama untuk menjaga SSK dituangkan dalam memorandum of understanding (MOU) diantara institusi yang terlibat, namun hal ini tetap tidak dapat mengikat institusi terkait baik secara by nature maupun hukum dalam menyelesaikan krisis (Cihak, 2010). Berikut beberapa hal yang mendukung diberikannya peran memelihara stabilitas sistem keuangan kepada bank sentral: 309 Respon dan Sinergi Kebijakan Bank sentral dapat memberikan respon kebijakan yang lebih tepat dalam hal terjadi vulnerabilities yang dipicu oleh sektor keuangan, seperti credit boom dan bubble harga asset. Dalam hal ini, respon kebijakan yang lebih tepat akan sulit dilakukan apabila bank hanya fokus pada tujuan mencapai stabilitas harga. Disamping itu, adanya peran bank sentral dalam SSK akan mendorong sinergi yang lebih baik antara perumusan kebijakan moneter dan kebijakan pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial). Dalam merespon krisis, sinergi kebijakan moneter dan prudential policy sangat dibutuhkan untuk memitigasi risiko sistemik. Mitigasi Risiko Sistemik Risiko yang bersifat sistemik apabila tidak diantisipasi dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi. Blinder (2010) menginterpretasikan definisi “mengatur risiko sistemik” dan “memelihara SSK” sebagai 2 (dua) hal yang hampir sama. Menurut Blinder terdapat 2 (dua) konsep systemic risk, yaitu: Pertama, sekumpulan lembaga keuangan skala besar akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila terdapat kesalahan operasional pada lembaga keuangan tersebut sehingga dapat secara signifikan mengganggu sistem keuangan (too big to be allowed to fail messily/ Systemically Important Financial Institutions/SIFI). Kedua, sekumpulan lembaga keuangan dalam jumlah banyak akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik apabila lembaga keuangan tersebut berperilaku sama. Sebagai contoh di krisis sistem perbankan di Indonesia pada tahun 1997/1998 yang dimulai dengan jatuhnya beberapa bank kecil. Dalam kasus lainnya, risiko sistemik dapat dialami oleh suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan besar dalam sistem pembayaran dan setelmen.Sebagai contoh, meskipun NYSE Euronext bukan perusahaan yang sangat besar, namun kegagalan yang dialami perusahaan ini dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat ditoleransi. 310 Berdasarkan konsep sistemik tersebut, potensi risiko sistemik perlu dipantau agar tidak menimbulkan instabilitas keuangan.Dengan melihat cakupan lembaga keuangan sistemik yang sangat luas, bank sentral perlu memantau tidak hanya perbankan namun juga institusi keuangan lainnya dan pasar keuangan yang dapat berpotensi sistemik. Blinder berpendapat bahwa mengingat keterkaitan erat antara upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dengan upaya pencapaian kestabilan moneter, peran pemantauan sebagai systemic risk regulator perlu dimandatkan kepada bank sentral dan peran ini harus dinyatakan secara eksplisit (Diagram 1). Diagram 1. Spektrum Tanggung Jawab Bank Sentral Sebagian para ahli berpendapat bahwa tanggung jawab dalam bidang kebijakan moneter adalah sepenuhnya dalam kendali bank sentral sementara tanggung jawab lainnya dilakukan oleh lembaga terpisah. Namun, Blinder berpendapat bahwa pemisahan tugas-tugas diluar kebijakan moneter justru mengabaikan konsep economies of scope. Tugas memelihara SSK berkaitan erat dengan upaya mencapai tujuan di bidang moneter melalui penstabilan output dan inflasi. Menurut Blinder bukan tindakan yang logis dan bijaksana untuk memisahkan tanggung jawab di bidang SSK (macroprudential) dengan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan microprudential khususnya lembaga keuangan skala besar yang berdampak sistemik (large systemically important financial institutions).Hal ini dilatarbelakangi bahwa kegiatan operasional dan keuangan dari SIFI tersebut dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dengan kata lain, potensi systemic risk dapat diminimalisasi apabila masing-masing SIFI beroperasi secara baik dan sehat. Disamping itu, mengingat SIFI tersebut berskala besar dan dimungkinkan saling terkoneksi secara politis, regulator untuk SIFI haruslah independen dari intervensi politik. 311 Berbagai pertimbangan tersebut mengarahkan pada pemberian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan moneter, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan systemic regulator kepada bank sentral. Sementara itu, economies of scope antara pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan skala besar dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan skala kecil cenderung tidak ada. Dibandingkan lembaga keuangan skala besar, lembaga keuangan skala kecil memiliki karakteristik neraca, profil risiko, dan struktur manajemen yang berbeda satu sama lain. Lembaga keuangan skala besar berorientasi global, sementara lembaga keuangan skala kecil cenderung berorientasi lokal. Karena beberapa pertimbangan tersebut, pengawasan lembaga keuangan skala kecil dapat dilakukan oleh institusi/ otoritas mana saja, meski saat ini umumnya di beberapa negara fungsi mikroprudensial masih berada di bawah bank sentral karena meskipun skalanya kecil tapi apabila berperilaku sama dapat memberikan risiko sistemik juga, seperti krisis di Indonesia 1997/1998. Mandat Stabilitas Sistem Keuangan di Beberapa Bank Sentral Secara umum tujuan bank sentral dibedakan menjadi dua, yaitu single objectives (price stability) dan dual objective (price stability dan financial stability)atau multi objectives (financial stability, payment system stability, economy growth, dll).Dalam perkembangan yang terjadi, terdapat beberapa bank sentral yang secara eksplisit menuangkan mandat stabilitas sistem keuangan baik sebagai tujuan maupun tugas dalam undang-undang bank sentral. Beberapa bank sentral tersebut adalah sebagai berikut: 312 Tabel 1Mandat Stabilitas Sistem Keuangan di Beberapa Bank Sentral Bank Sentral Tujuan/Tugas Bank Negara Malaysia “…to promotemonetary stability and financial stability conduducive to the sustainable growth of the Malaysian economy. “ Bank of England “…an objective of the bank shall be to contribute to protecting and enhancing the stability of the financial system of the United Kingdom” Bank of Japan Bank of Thailand “… to ensure smooth settlement of fund among banks and other financial institutions, thereby contributing to the maintenance of stability of financial system.” “…to maintain monetary stability, financial institution system stability and payment system stability.” Monetary Authority of Singapore “…to foster a sound and reputable financial centre” Reserve Bank of Australia “…has a number of functions and powers, and undertakes a number of activities, for what are broadly “financial stability” purposes, including : banking system oversight, non-bank deposit takers, insurance sector, payment system oversight, financial stability and market analysis” 6XPEHUZHEVLWHGLPDVLQJPDVLQJEDQNVHQWUDO Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cihak (2007), sebagian besar bank sentral di berbagai negara melaksanakan peran di bidang stabilitas sistem keuangan didasarkan pada interpretasi undang-undang (bukan legal basis). Seiring dengan perkembangan yang ada, saat ini sudah banyak bank sentral yang mempunyai fungsi di bidang stabilitas sistem keuangan dan 313 makroprudensial.Hasil survei yang dilakukan IMF mengungkapkan bahwa meski hanya sedikit bank sentral yang memiliki mandat di bidangstabilitas sistem keuangan, namun perhatian bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan semakin meningkat.Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan negara yang menerbitkan Financial Stability Report (FSR).Hingga saat ini tercatat 60 negara (24 negara maju dan 36 negara berkembang),telah menerbitkan FSR secara periodik. FSR tersebut merupakan bentuk akuntabilitas bank sentral terhadap pelaksanaan fungsi stabilitas sistem keuangan. Hasil kedua survei dapat dilihat pada halaman lampiran. Komite Stabilitas Sistem Keuangan Implikasi diberikannya mandat stabilitas sistem keuangan memerlukan good governance yang mendukung akuntabilitas dari implementasi mandat tersebut. Secara ideal, akuntabilitas pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial dapat dilakukan dengan pembentukan sebuah komite/ forum sebagai wadah institusional dalam rangka pengambilan respon kebijakan. Komite ini beranggotakan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan makroprudensial, seperti otoritas moneter, otoritas fiskal, dan otoritas pengawasan lembaga keuangan/pasar keuangan. Komite ini berwenang mengambil keputusan kebijakan dan sekaligus memiliki fungsi koordinasi di bidang stabilitas sistem keuangan. Salah satu bank sentral yang menerapkan mekanisme governance ini adalah BNM. Dengan dual mandat di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan, BNM memisahkan governance pengambilan keputusan di bidang kebijakan moneter dan pengambilan keputusan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan melalui 2 komite, yaitu Monetary Policy Committe (MPC) dan Financial Stability Executive Committee (FSEC). FSEC diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan 1 Deputi Gubernur, dan 3- 5 orang anggota dari jajaran direktur atau pihak lain, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Board. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak eksternal yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang stabilitas sistem keuangan dan mampu memberikan penilaian yang obyektif. 314 Pada prakteknya, saat ini terdapat 2 pihak eksternal yang duduk sebagai anggota FSEC dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum dan accounting. Dalam hal issue atau permasalahan yang dibahas dalam FSEC melibatkan institusi keuangan lain diluar yang diawasi oleh BNM (selain bank dan asuransi) dan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BNM, maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari MoF harus diinfokan dan menghadiri pertemuan FSEC dimaksud. Disamping itu, apabila rekomendasi kebijakan yang dibahas dalam pertemuan FSEC ditujukan untuk orang atau lembaga keuangan dibawah pengawasan otoritas lain, maka kepala otoritas pengawasan tersebut harus diundang di dalam rapat FSEC. Dalam hal ini, kehadiran Sekjen dan kepala otoritas pengawasan atau perwakilan yang ditunjuk adalah sebagai anggota dari FSEC. Validitas keputusan yang diambil dalam pertemuan FSEC harus memenuhi kuorum, yaitu 3 anggota, termasuk Gubernur. 4. Implementasi di Bank Indonesia a. Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, terdapat 4 (empat) strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu (i) pemantapan regulasi dan standar, (ii) penguatan riset, surveillance, (iii) peningkatan koordinasi dan kerjasama, dan (iv) jaring pengaman dan resolusi krisis. Setiap strategi dilakukan melalui berbagai instrumen yang terdapat dalam setiap pilar. 315 Perkembangan dan tingkat kompleksitas sektor keuangan yang tinggi ditambah pengalaman krisis semakin menyadarkan Bank Indonesia akan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di bidang surveillance, Bank Indonesia secara kontinyu mengembangkan berbagai metodologi, antara lain stress test, probability of default, dashboard macroprudential surveillance, dan FSI, untuk melakukan deteksi dini sumber kerawanan di sektor keuangan.Meski tidak melakukan pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan non bank, Bank Indonesia melakukan surveillance terhadap lembaga keuangan non bank (seperti Asuransi dan perusahaan pembiayaan), pasar modal dan sektor riil (rumah tangga dan korporasi).Macrosurveillance ini perlu dilakukan oleh Bank Indonesia karena disadari bahwa potensi risiko di sistem keuangan dapat bersumber dari sektor keuangan manapun. Dalam rangka memantau potensi risiko sistemik, Bank Indonesia juga memonitor sistem pembayaran yang berfungsi mengalirkan dana dalam sistem keuangan melalui mekanisme kliring dan RTGS. Sementara itu, di bidang pengawasan dan regulasi perbankan Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Berbagai upaya tersebut antara lain: 316 Perbaikan sejumlah regulasi perbankan yang mengedepankan aspek prudential, kelembagaan, governance, dan manajemen risiko, misal ketentuan Fit and Proper, Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan Good Corporate Governance. Paradigma pengawasan yang lebih berbasis risiko (risk based supervision) Peningkatan tingkat compliance dengan standar internasional (BCP dan IAS) Menambah jumlah pengawas bank dan meningkatkan kompetensi pengawas melalui program sertifikasi Penguatan struktur dan edukasi perbankan melalui implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang SSK, Bank Indonesia menghasilkan beberapa publikasi antara lain Kajian Stabilitas Keuangan (KSK), Laporan Pengawasan Perbankan (LPP), dan berbagai hasil riset. KSK diterbitkan secara semesteran dan didiseminasikan dalam bentuk publikasi cetak dan website. Secara garis besar, KSK mengulas (i) hasil assessment sektor keuangan selama periode laporan, (ii) penjabaran sumber kerawanan (vulnerabilities) yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan, (iii) perkembangan sektor keuangan dan infrastruktur keuangan, (iv) prospek sistem keuangan ke depan, dan (v) topik khusus dan hasil riset terkait stabilitas sistem keuangan. KSK yang diterbitkan semakin memperjelas akuntabilitas Bank Indonesia dalam rangka stabilitas sistem keuangan, karena tidak hanya sekedar laporan, namun juga dilengkapi dengan himbauan kepada pelaku perbankan dan pasar keuangan untuk memitigasi risiko yang dihadapi. b. Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia telah melaksanakan fungsi makroprudensial sejak didirikannya Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan penerbitan KSK pada tahun 317 2003, pelaksanaan fungsi makroprudensial/stabilitas sistem keuangan di Bank Indonesia menjadi semakin diperjelas. Instrumen makroprudensial yang telah diimplementasikan, antara lain PPAP, CAR dan bersama Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) menyusun kebijakan PDN dan GWM – LDR.Bauran instrumen kebijakan moneter dan instrumen kebijakan makroprudensial berperan penting dalam upaya menjaga kestabilan perekonomian nasional mengingat perbankan masih merupakan jalur utama bagi terlaksananya kebijakan moneter. Pengambilan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia didukung oleh beberapa faktor, yaitu: Seperti bank sentral pada umumnya, Bank Indonesia dilengkapi dengan berbagai tools yang dapat dengan cepat mampu memitigasi risiko sistemik. Fungsi surveillance sistem keuangan (macrosurveillance) telah dilakukan oleh Bank Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BSSK. Assessment dan monitoring terhadap potensi risiko di sistem keuangan tersebut mencakup sektor perbankan, non bank, dan sektor riil. Terkait hal ini, Bank Indonesia juga telah mengembangkan berbagai metodologi yang ditujukan untuk melakukan assessmentpotensi risiko di sektor keuangan, antara lain stress test, FSI, dan probability of default. Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang pengawasan bank dan sistem pembayaran sehingga dapat secara cepat mendeteksi potensi terjadinya risiko sistemik. 5. Kesimpulan Upaya nyata sedang dilakukan terkait dengan krisis keuangan 20082009. Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah perlunya kerangka kebijakan yang memiliki jangkauan luas untuk memelihara kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan makroprudensial. 318 Kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi risiko keuangan yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, dalam implementasinya kebijakan makroprudensial harus dilengkapi dengan berbagai perangkat yaitu tujuan, cakupan analisis, kewenangan dan piranti serta tata kelolanya (termasuk komite kebijakan stabilitas keuangan). Bank sentral khususnya sebagai lembaga yang memiliki piranti (penyediaan likuiditas) dan keahlian misalnya di dalam analisa pasar keuangan dan dampak sistemik, dituntut untuk berperan besar. Oleh karena itu Bank Indonesia perlu diberikan mandat secara eksplisit di bidang stabilitas sistem keuangan. Mandat ini perlu diformalkan dalam undangundang bank sentral. Keterkaitan yang erat antara mandat dan fungsi bank sentral dan lembaga otoritas pengawasan lain dalam pencegahan dan penanganan krisis perlu diwujudkan dalam suatu mekanisme koordinasi yang kuat. Di Indonesia, koordinasi tersebut akan diwujudkan dalam suatu undangundang yang disebut Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Pengaturan yang jelas dan kredibel tersebut diperlukan sehingga tujuan stabilitas sistem keuangan dapat tercapai. 319 6. Referensi Acharya, V. V. (2009). “A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation.” Journal of Financial Stability, Forthcoming. Basel Committee on Banking Supervision (2010). “Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System, December. Besar, D., P. Booth, K. K. Chan, A. Milne and J. Pickles (2010). “Systemic Risk in Financial Services”, British Actuarial Journal 14. Blinder, A.S.(2010). “How Central Should the Central Bank Be?,” Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 48(1), pages 123-133, March. Brockmeijer, et.al, (2011). “Macroprudential Policy: An Organizing Framework”. Washington, International Monetary Fund. Brunnermeier, M. K. (2009). “Deciphering the 2007-08 liquidity and credit crunch.” Journal of Economic Perspectives Caprio, G. and D. Klingebiel (2003). Episodes of systemic and borderline financial crises.Managing the Real and Fiscal Effects of Banking Crises. D. Klingebiel and L. Laeven: 31-49. Cihak, M.P. Madrid, and L. Ong, (2011).”IMF Guide to Stress Testing”. International Monetary Fund: Washington, DC. Claessens, S., D. Klingebiel, et al. (2004). “Resolving systemic crises: policies and institutions.” Policy Research Working Paper Series The World Bank 3377. Committee on the Global Financial System (2010). “Macroprudential instruments and frameworks: A Stocktaking of Issues and Experiences”. CGFS Papers No. 38. Goodhart, C. (2010). “The Changing Role of Central Banks”. BIS Working Paper No. 326. 320 Kane, E. J. (2008). “Resolving systemic financial crises efficiently.” PacificBasin Finance Journal 10(2002): 217- 226. Kashyap, A. K., R. G. Rajan, et al. (2008). Rethinking capital regulation. Maintaining Stability in a Changing Financial System.Jackson Hole, Wyoming, Federal Reserve Bank of Kansas City. Laeven, L. and F. Valencia (2008). “Systemic banking crises: A new database.” IMF Working Paper 224. Milne, A. (2009). The fall of the house of credit.Cambridge, CambridgeUniversity Press. Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff (2008a). “Is the 2007 US sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison.” American Economic Review 98(2): 339-344. Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff (2008b).”Banking crises: An equal opportunity menace.” NBER working paper series. Reinhart, C. M. and K. S. Rogoff (2009).”The aftermath of financial crises.” NBER working paper series. Turner, Adair (2009) “The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis”, the UK Financial Services Authority, March and published as a .pdf on www.fsa.gov.uk/pages/Library/Corporate/ turner/index.shtml 321 322 MENGINTEGRASIKAN KEBIJAKAN MONETER DAN MAKROPRUDENSIAL: MENUJU PARADIGMA BARU KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA PASCAKRISIS GLOBAL Juda Agung Abstrak: Krisis ekonomi global telah memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter tidak cukup untuk mencapai stabilitas makroekonomi, mengingat instabilitas makroekonomi semakin banyak bersumber dari sektor keuangan. Paper ini mencoba membuka wacana bagi paradigma baru kebijakan moneter di Indonesia pascakrisis global. Esensi dari paradigma baru tersebut adalah pentingnya mengintegrasikan kebijakan makroprudensial ke dalam kerangka kebijakan moneter inflation targeting yang telah diimplementasikan di Bank Indonesia sejak lima tahun yang lalu. Paper ini juga menggarisbawahi beberapa implikasi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, baik dalam konteks formulasi kebijakan moneter maupun implementasi kebijakan makroprudensial, termasuk mandat institusional Bank Indonesia ketika fungsi pengawasan dipisahkan dari Bank Indonesia. ------------------------Paper ini merupakan versi pendek dari paper yang dibuat dalam rangka Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan 29, 2010. 323 1. Pendahuluan Bagi pembuat kebijakan seperti Bank Indonesia, krisis ekonomi dan keuangan adalah suatu kejadian mahal yang dapat digunakan untuk melakukan refleksi, mengambil pelajaran atas kejadian yang baru saja dilewati, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas apa yang dilakukan selama ini. Sebagaimana halnya krisis-krisis ekonomi sebelumnya, krisis ekonomi dan keuangan global yang saat ini sedang dalam proses pemulihan memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi otoritas moneter. Pelajaranpelajaran yang dapat dipetik mempunyai implikasi yang penting bagi perbaikan-perbaikan atas kerangka kebijakan moneter yang selama ini kita pahami dan kita gunakan. Pelajaran yang paling berharga dari krisis ekonomi global bagi otoritas moneter adalah bahwa upaya menjaga stabilitas perekonomian makro tidak cukup dengan menjaga stabilitas harga. Pelajaran ini muncul karena fakta menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir semakin banyak bersumber dari sektor keuangan. Dalam krisis global yang baru kita lewati, krisis yang bermula di sektor keuangan terjadi ketika dunia berhasil mencapai prestasi terbaiknya dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah era yang seringkali disebut oleh para ekonom sebagai era “Great Moderation”. Era ini ditandai oleh stabilitas harga di hampir semua negara maju dan berkembang. Banyak yang mengklaim bahwa bahwa era great moderation ini sebagai buah dari semakin kuatnya kerangka kebijakan moneter di negara maju dan berkembang, ditandai dengan tren digunakannya Inflation Targeting Framework dan didukung bank sentral yang independen. Namun, stabilitas harga ternyata tidak menjamin stabilitas keuangan dan makroekonomi. Faktanya, ia justru seringkali mendorong risiko terjadinya pertumbuhan kredit yang berlebihan dan terciptanya gelembung harga aset yang didorong oleh perilaku search for yield yang berlebihan – sebuah kondisi yang sering disebut sebagai “paradoks kredibilitas”. Kondisi makroekonomi yang stabil yang ditandai oleh inflasi dan suku bunga rendah yang berlangsung lama telah menciptakan moral hazard dari 324 pelaku pasar terhadap risiko makroekonomi. Mereka merasa risiko dari sisi makroekonomi ini sudah dijamin oleh bank sentral yang kredibel, sehingga cenderung mengejar aset-aset yang lebih berisiko dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Di Indonesia, dalam satu dasawarsa terakhir ini, tekanan terhadap stabilitas makroekonomi juga semakin sering bersumber dari sektor keuangan. Krisis Asia yang menghantam Indonesia juga bermula di sektor perbankan dan sektor korporasi yang over-leverage dipicu oleh optimisme yang berlebihan dan moral hazard yang timbul dari “jaminan” atas stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar yang relatif tetap. Krisis di akhir tahun 2008 juga lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor di sektor keuangan, daripada karena ketidakseimbangan internal dan eksternal di perekonomian makro kita. Inflasi ketika itu berada dalam tren menurun, neraca berjalan juga berada dalam kondisi surplus. Namun, arus modal masuk yang sebelumnya cukup tinggi mengering secara tiba-tiba akibat proses “deleveraging” pasca penutupan Lehman Brothers. Risiko antar bank meningkat, likuiditas mengetat, pertumbuhan kredit turun secara drastis dari 38% di akhir triwulan III-2008 menjadi 10% di akhir tahun 2009. Boom-bust dari pertumbuhan kredit seiring dengan siklus kepercayaan ini pada akhirnya semakin memperbesar fluktuasi perekonomian. Secara inheren perilaku bank memang “prosiklikal”, optimisme yang berlebihan ketika perekonomian sedang membaik, berbalik menjadi sangat risk-averse yang berlebihan ketika terjadi pelemahan ekonomi. Kedua, perilaku ini juga seringkali diperparah oleh regulasi yang bekerja secara prosiklikal, yaitu mendorong pertumbuhan kredit di saat pertumbuhan ekonomi membaik dan sebaliknya mendorong pengetatan kredit saat perekonomian melemah. Regulasi perbankan yang lebih difokuskan pada kesehatan individu bank ini seringkali tidak kompatibel dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter yang berorientasi pada inflasi yang rendah, seperti Inflation Targeting Framework tidaklah cukup. 325 Dia perlu didukung oleh adanya sebuah instrumen regulasi prudensial di sektor perbankan yang didisain untuk menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan – sebuah instrumen yang sering disebut sebagai kebijakan makroprudensial. Dalam konteks ini, bank sentral harus selalu memperhatikan interaksi antara sektor finansial dan sektor riil. Mengabaikan interaksi ini dapat menyebabkan bank sentral menjadi cenderung memandang rendah risiko di sektor keuangan ketika makroekonomi dalam kondisi yang stabil, dan cenderung memandang berlebihan terhadap risiko di sektor keuangan ketika dihadapkan pada kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Artinya, perlu sebuah sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial yang berperan menekan prosiklikalitas mendukung kebijakan moneter untuk mengurangi fluktuasi output. Mengintegrasikan aspek makroprudensial ke dalam kebijakan moneter, membawa implikasi pada perlunya melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kerangka kebijakan moneter. Bagaimana memasukkan makroprudensial kedalam framework kebijakan moneter? Apa implikasi bagi formulasi kebijakan moneter? Apakah mandat BI untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah mencakup upaya menjaga stabilitas sistem keuangan? Bagaimana implikasi penting bagi proses pemisahan fungsi pengawasan bank beralih ke OJK, ketika akses pada pengaturan makroprudensial berpotensi mengalami hambatan? Makalah ini akan mencoba membuka pemikiran tentang perlunya sebuah paradigma baru dalam kebijakan moneter pascakrisis global. Paper ini akan melihat implikasi pada kerangka kebijakan moneter inflation targeting framework yang sekarang diterapkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Bab 2 memaparkan mekanisme terjadinya prosiklikalitas dan stylized fact prosiklikalitas dari sistem keuangan di Indonesia sebagai landasan berfikir. Bab 3 memaparkan paradigma baru tentang peran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menciptakan stabilitas makroekonomi. Bab 4 membahas implikasi pada keranga kerja ITF. Bab 5 memaparkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. 326 2. Sistem Keuangan dan Prosiklikalitas di Indonesia Mekanisme Prosiklikalitas Sistem Keuangan Perilaku sistem keuangan yang sangat menentukan stabilitas makroekonomi adalah peranannya dalam menciptakan prosiklikalitas yang berlebihan. Prosiklikalitas adalah perilaku sistem keuangan yang mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi. Dengan perilakunya yang prosiklikal, sistem keuangan meningkatkan ketidakstabilan makroekonomi dengan menciptakan fluktuasi output. Sistem keuangan memang secara inheren berperilaku prosiklikalitas karena pasar keuangan yang selalu ditandai oleh informasi yang asimetri menyebabkan terjadinya “financial accelerator”. Dengan karakteristik pasar seperti itu, ketika perekonomian mengalami kontraksi dan nilai kolateral turun, maka perusahaan berkualitas baik dengan proyek yang menguntungkanpun akan sulit mendapatkan kredit. Sebaliknya ketika perekonomian membaik dan nilai kolateral naik, maka perusahaan ini kembali mendapatkan akses ke bank dan ini menambah stimulus pada perekonomian. Walaupun financial accelerator merupakan mekanisme utama dari terjadinya prosiklikalitas, Borio et al (2002) menekankan pentingnya respon pelaku pasar yang tidak proporsional dalam menilai risiko turut memperparah prosiklikalitas. Oleh sebab itu, prosiklikalitas bukan hanya hasil interaksi antara siklus ekonomi/bisnis (business cycle) dan siklus keuangan (financial cycle), namun juga dipengaruhi oleh siklus perilaku terhadap risiko (risk-taking cycle), yaitu perilaku yang ditandai oleh optimisme yang berlebihan ketika siklus ekonomi membaik dan pesimisme yang berlebihan ketika siklus ekonomi memburuk. Siklus bisnis ditandai oleh fase ekspansi ketika perekonomian mengalami fase pertumbuhan dan fase kontraksi ketika perekonomian mengalami fase pelemahan. Siklus keuangan ditandai oleh perilaku perbankan yang lebih ekspansif dengan peningkatan leverage sejalan dengan fase ekspansi pada siklus bisnis. Sebaliknya, perilaku perbankan 327 menjadi lebih konservatif dengan deleveraging sejalan dengan fase kontraksi pada siklus bisnis. Interaksi antara siklus bisnis dan siklus keuangan ini ditentukan oleh perilaku dari agen ekonomi terhadap risiko (risk-taking cycle) yang juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap perekonomian ke depan, persepsi risiko, regulasi, dan insentif. Perubahan terhadap risiko ini yang menjelaskan mengapa perilaku investor dapat berubah secara drastis dari sangat optimis ketika risiko rendah menjadi sangat pesimis dengan menghindari risiko. Perubahan terhadap pengambilan risiko ini mendasari perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dari aktifitas di sistem keuangan dan aktifitas perekonomian. Interaksi dari ketiga siklus yang bergerak dengan arah yang sama dan saling memperkuat tersebut yang membentuk prosiklikalitas sektor keuangan (Tabel 1, Gambar 1). Interaksi ketiganya dapat digambarkan secara tipikal dalam konteks siklus boom-bust. Pada awalnya, ketika perekonomian bergerak dalam fase ekspansi yang ditandai oleh stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan meningkat, keyakinan investor meningkatkan optimisme dalam melihat perekonomian. Hal ini mendorong perilaku yang cenderung mengambil risiko tinggi, yang mendorong kenaikan permintaan kredit dan harga aset. 328 Tabel 1. Interaksi antara siklus bisnis, perilaku terhadap risiko dan siklus keuangan Siklus Bisnis Siklus Perilaku Risiko x Meningkatnya keyakinan dan optimisme Fase Ekspansi x Stabilitas makroekonomi x Pertumbuhan ekonomi naik x Meningkatnya perilaku ambil risiko (risk taking) x Permintaan terhadap kredit meningkat Siklus keuangan x Penilaian risiko turun, spread suku bunga turun x Harga aset naik mendorong nilai kolateral x Leverage meningkat x Arus modal masuk asing meningkat x Penyaluran kredit naik x Bank melakukan deleveraging x Meningkatnya volatilitas makro Fase Kontraksi x Menurunnya aktivitas perekonomian x Loan loss provix Menurunnya sion naik keyakinan pelaku pasar x Spread suku bunga naik x Risk averse x Permintaan kredit menurun x Penyaluran kredit turun x Arus modal masuk menurun Sumber: Nijathaworn (2010), diedit. 329 Dalam periode yang optimis ini, risiko di sektor keuangan turun, spread suku bunga kredit turun, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif berkurang karena bank lebih melihat perspektif jangka pendek daripada perspektif jangka panjang. Kenaikan harga aset menyebabkan meningkatnya nilai kolateral sehingga mendorong peningkatan penyaluran kredit. Hal ini semakin mendorong keyakinan pelaku pasar dan memperbesar pengambilan risiko yang terefleksi pada meningkatnya leverage. Meningkatnya penyaluran kredit mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi dan rumah tangga untuk lebih banyak melakukan konsumsi sehingga semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika keyakinan terhadap perekonomian turun, perilaku investor berubah menjadi menghindari risiko. Dampaknya adalah harga aset turun, sehingga nilai kolateral jatuh. Bank merespon dengan “deleveraging”, menggeser portfolionya dari kredit yang berisiko tinggi kepada aset yang berisiko rendah, seperti SBI dan SUN, untuk menjaga kecukupan modalnya. Penyisihan cadangan juga ditingkatkan untuk mengantisipasi memburuknya kualitas kredit. Kondisi ini menurunkan penyaluran kredit yang pada gilirannya akan semakin memperburuk perekonomian. 330 Gambar 1. Interaksi siklus ekonomi, siklus keuangan dan siklus risiko pada fase ekspansi (kiri) dan kontraksi (kanan) Prosiklikalitas Sistem Keuangan di Indonesia: Stylized Fact Prosiklikalitas sistem keuangan yang berlebihan menciptakan ketidakstabilan makroekonomi. Berulangnya episode krisis dan peran sektor keuangan dalam memperburuk krisis yang terjadi mengharuskan Bank Indonesia untuk secara serius memikirkan kebijakan untuk memitigasi prosiklikalitas dari sistem keuangan di Indonesia. Di banyak negara emerging, seperti Indonesia, mengelola prosiklikalitas dari sistem keuangan pada dasarnya adalah mengelola prosiklikalitas sektor perbankan, karena perekonomian masih sangat tergantung pada perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi. Oleh sebab itu, mengendalikan prosiklikalitas sektor perbankan mempunyai implikasi yang penting bagi terciptanya stabilitas perekonomian makro. 331 Prosiklikalitas dapat dicermati dari perkembangan kredit perbankan dalam periode ekspansi dan kontraksi.1 Melihat perilaku pertumbuhan kredit, spread suku bunga, modal, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif selama periode-periode kontraksi dan ekspansi menunjukkan besarnya prosiklikalitas sistem perbankan di Indonesia. Grafik 1 menunjukkan hubungan antara rata-rata pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi. Dari grafik tersebut tampak bahwa kredit terlihat tumbuh jauh lebih cepat dari PDB selama periode ekspansi dan tumbuh jauh lebih lambat ketika terjadi perlambatan pertumbuhan. Sebagai contoh, selama periode ekspansi, PDB tumbuh di atas 6%, pertumbuhan kredit tumbuh rata-rata 25,8%. Namun, begitu pertumbuhan ekonomi dalam fase kontraksi, ketika PDB tumbuh 3-4%, kredit hanya tumbuh secara rata-rata 14,3%. Pada kondisi ekstrim ketika pertumbuhan PDB di bawah 3%, kredit secara rata-rata tumbuh -12,3%. Grafik 1. Hubungan antara rata-rata kredit dan PDB (1990-2009) 1 Observasi menggunakan data setelah krisis 1997/1998, mengingat data sejak krisis 1997/1998 sampai dengan 2000 terdistorsi oleh kredit yang dialihkan ke BPPN. 332 Selanjutnya, dengan melihat pertumbuhan PDB dan kredit dari waktu ke waktu (Grafik 2), tampak bahwa adanya hubungan yang erat antara pertumbuhan PDB riil kredit riil. Kredit riil bergerak secara prosiklikal dan tumbuh lebih cepat dari PDB ketika periode-periode ekspansi dan tumbuh melambat lebih besar dari PDB ketika periode-periode kontraksi. Sebagai contoh, pascakrisis 1997/1998, berlangsungnya “credit crunch” yaitu risk averse dari perbankan untuk meyalurkan kredit semakin memperburuk proses pemulihan ekonomi di Indonesia yang berjalan sangat lambat. Agung et al (2001) menunjukkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya credit crunch, seperti “capital crunch”, persepsi risiko yang masih tinggi di sektor dunia usaha, dan masalah informasi yang asimetri. Setelah itu, sejak awal 2002 kredit secara gradual tumbuh cukup tinggi sebelum akhirnya mengalami penurunan yang tajam sejalan dengan melemahnya perekonomian pasca kenaikan harga BBM di tahun 2005. Setelah mencapai titik terendah di tahun 2006, kredit berangsur-angsur meningkat sampai mencapai puncaknya di tahun 2008 ketika sempat mencapai pertumbuhan tertinggi mencapai 38% pada Triwulan III-2008. Periode ini adalah merupakan ilustrasi yang sempurna dari episode siklus upswing dari perekonomian didorong oleh kenaikan harga komoditas internasional dan didorong keyakinan dari pelaku ekonomi, baik sektor perbankan maupun sektor riil. Dalam periode optimis ini, bank biasanya memandang rendah risiko seperti tercermin dari menyempitnya spread suku bunga. 333 Grafik 2. Prosiklikalitas kredit perbankan Ketika perekonomian melemah setelah krisis global menghantam perekonomian Indonesia, keyakinan bank mengalami penurunan sehingga mendorong sikap kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Sejak triwulan IV-2008, bank menjadi bersikap risk averse dengan melakukan deleveraging dengan menurunkan penyaluran kredit dari yang semula cukup agresif dalam melakukan ekspansi kredit. Sikap kehati-hatian bank dan kekhawatiran terjadinya peningkatan kredit bermasalah mendorong bank untuk menempatkan dananya pada aset dengan resiko rendah seperti, SBI, SUN dan FASBI. Hal itu terlihat dari meningkatnya porsi surat-surat berharga terhadap aktiva produktif, sebaliknya porsi kredit mengalami penurunan (Grafik 3). Menurunnya keyakinan bank dan sikap risk averse juga mendorong bank meningkatkan spread suku bunga kredit (Grafik 4). Masih tingginya yield dari aset tanpa risiko (risk-free assets), seperti SUN juga menyebabkan dalam periode downswing ketika risiko meningkat, riskadjusted return kredit menjadi kurang menarik jika dibandingkan dengan SUN. Hal ini menyebabkan bank cenderung menggeser portfolio kreditnya ke aset berisiko rendah. Insentif untuk melakukan pergeseran portfolio ke aset yang berisiko rendah ini semakin didorong oleh rendahnya ‘trade 334 off’ antara risk dan return antara pilihan portfolio kredit dan surat-surat berharga. Apabila kita lihat profitabilitas bank pada tahun 2009, ketika pertumbuhan penyaluran kredit mengalami penurunan, keuntungan bank justru mengalami kenaikan.2 Grafik 3. Portfolio Aset Bank Grafik 4. Spread Suku Bunga Kredit 2 Lihat Laporan Perekonomian Indonesia 2009, Bab 4. 335 Apabila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, prosiklikalitas di di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Tabel 2 menunjukkan prosiklikalitas dari beberapa negara di Asia yang diukur dari koefisien korelasi antara PDB dan kredit riil.3 Ada sejumlah karakteristik sistem keuangan di Indonesia yang dapat memperparah prosiklikalitas. Pertama, keterbatasan alternatif sumber pembiayaan nonbank. Sistem keuangan Indonesia sangat tergantung pada bank sebagai sumber pembiayaan eksternal. Belum berkembanganya pasar modal adalah salah satu karakteristik sistem keuangan di Asia (Roldos et al, 2004). Dibandingkan dengan negara-negara kawasan, pembiayaan yang bersumber dari luar perbankan di Indonesia relatif rendah. Dengan sistem seperti ini, apabila suplai kredit perbankan mengalami masalah, perusahaan sulit untuk mendapatkan alternatif pembiayaan, sehingga memperparah prosiklikalitas. Kedua, peran bank asing yang semakin signifikan dalam perekonomian Indonesia dapat meningkatkan prosiklikalitas terutama apabila bank asing tersebut merupakan kantor cabang. Kantor cabang bank asing yang eksposur kreditnya ditentukan oleh kantor pusat cenderung mengurangi portfolio kreditnya di Indonesia ketika periode downswing (country risk meningkat), dan sebaliknya menambah portfolio kredit ketika country risk turun sehingga menambah prosiklikalitas perekonomian. Ketiga, ketergantungan yang berlebihan pada kolateral dalam memitigasi risiko kredit. Kenaikan nilai kolateral pada periode ekspansi menyebabkan bank melakukan ekspansi kredit pada debitur yang beresiko tinggi. Namun ketika perekonomian terkontraksi dan nilai kolateralnya turun menyebabkan bank menekan penyaluran kredit. Keempat, arus modal masuk yang umumnya prosiklikal, yaitu mengalir masuk ketika prospek ekonomi membaik dan mengalir keluar begitu prospek memburuk memperparah prosiklikalitas perekonomian Indonesia. 3 Lihat Craig, et al (2005). 336 Tabel 2. Prosiklikalitas kredit riil dan PDB riil beberapa negara Asia Negara Koefisien korelasi* Indonesia 0.82 Malaysia 0.51 Phillipines 0.33 Thailand 0.32 Australia 0.26 Jepang 0.48 China 0.31 Hongkong SAR 0.30 Sumber: Craig, et al (2006). * koefisien korelasi kredit dan PDB riil. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk memitigasi prosiklikalitas. Paling tidak ada tiga instrumen yang dimiliki bank sentral untuk dapat digunakan untuk memitigasi prosiklikalitas sistem keuangan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan nilai tukar dan arus modal. Isu ini menjadi inti pembahasan dalam bab 3. 3. Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Namun, menjaga stabilitas harga tidaklah cukup untuk menjamin tercapainya stabilitas makroekonomi, karena sistem keuangan yang berperilaku prosiklikal menyebabkan fluktuasi perekonomian yang berlebihan. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan moneter dapat secara efektif menjaga stabilitas makroekonomi. 337 Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan Isu penting dalam konteks peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah bagaimana bank sentral merespon ketidakseimbangan yang terjadi di sektor keuangan (financial imbalances). Isu yang telah lama menjadi perdebatan ini muncul kembali setelah krisis global karena adanya argumen bahwa krisis global yang terjadi sebagaian disebabkan oleh kebijakan moneter yang melakukan pembiaran terjadinya akumulasi imbalances dan kenaikan harga aset yang berlebihan. IMF (2009), misalnya, mengatakan bahwa pendekatan ”benign neglect” seperti itu telah menyebabkan moral hazard dan speculative booms yang menyebabkan kenaikan harga aset jauh melebihi fundamentalnya. Dalam perdebatan ini, ada dua pendapat yang berseberangan, yaitu “clean” vs “lean” approach atau pendekatan pasif vs aktif. Pandangan pertama, pendekatan aktif mengatakan bahwa bank sentral seharusnya fokus pada inflasi. Harga-harga aset perlu dimonitor sepanjang mengandung informasi mengenai kondisi perekonomian, namun bank sentral tidak perlu merespon kenaikan harga aset tersebut itu sendiri. Pandangan ini didasarkan pada dua argumen. Pertama, tidak mudah membedakan antara kenaikan harga aset yang disebabkan oleh spekulasi dengan yang disebabkan oleh optimisme yang masih rasional. Kedua, kebijakan moneter terlalu tumpul untuk menghentikan kenaikan harga aset dan intervensi kebijakan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pandangan ini mengatakan lebih baik merespons dampak dari bubble secara ex post, daripada mencegah berkembangnya asset bubble secara ex ante. Kenaikan harga aset akibat spekulasi memang tidak mudah diidentifikasi dengan pasti. Namun, lebih baik melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya krisis daripada bersikap pasif dan membiarkan berkembangnya kegiatan spekulatif yang mengarah kepada skenario krisis. Membatasi peran bank sentral untuk sekedar pasif ketika pertumbuhan kredit melambung tinggi dan membiarkan harga aset menggelembung menjadi bubble kemudian ‘membersihkan piring sehabis pesta berakhir’ adalah sesuatu yang naif. Hal ini akan menciptakan moral hazard dari 338 pelaku pasar. Selama pelaku pasar tahu bahwa bank sentral tidak akan mengerem kenaikan harga aset, mereka akan terus mendorong harga aset. Apalagi ketika mereka tahu bahwa ada jaminan dari bank sentral akan menyediakan likuiditas yang cukup ketika krisis terjadi. Hal tersebut mendorong munculnya argumen sebaliknya, yaitu bank sentral seharusnya “leaning againts the wind”, melakukan respon terhadap ketidakseimbangan di sektor keuangan. Argumen ini telah banyak dikemukakan utamanya oleh Bank for International Settlement (BIS) jauhjauh hari sebelum global terjadi4 dan oleh International Monetary Fund5 setelah krisis global, yang secara jelas mengatakan bahwa: “There is now a stronger case for monetary policy decisions to be based on a framework that incorporates the longer-term implications of asset-price booms for inflation and economic growth” (IMF, 2009). Argumennya adalah bank sentral dapat menggunakan instrumen suku bunga lebih dari yang diperlukan oleh inflasi dan output gap apabila menghadapi pertumbuhan kredit yang terlalu cepat dan laju kenaikan yang kencang dari harga aset.6 Artinya, walaupun inflasi kelihatannya terkendali, bank sentral dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter apabila ada tanda-tanda berkembangnya bubble, tercermin dari kenaikan yang tajam dari pemberian kredit, meningkatnya leverage pada institusi keuangan, neraca perusahaan, dan rumah tangga, maupun harga-harga asset, termasuk stok dan properti. Dengan kata lain, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kebijakan moneter harus berperan secara “simetris”, bukan saja merespon ketika fase bust, namun juga pada saat fase boom dari siklus ekonomi dan keuangan. Bagi bank sentral, boom dan bust dari harga aset tidak hanya dapat dilihat sebagai bubble dari harga aset itu sendiri, namun harus dilihat 4 5 6 Borio and White (2003) IMF (2009) Beberapa studi mencoba memasukkan harga aset ke dalam loss function dari bank sentral bersama dengan inflasi dan output gap. 339 dalam konteks yang lebih fundamental sebagai gejala-gejala meningkatnya leverage dan pertumbuhan akumulasi kapital yang tinggi. Dalam periode ekspansi, optimisme terhadap imbal hasil ke depan mendorong kenaikan harga aset, memicu para pelaku untuk meminjam lebih banyak dalam rangka membiayai akumulasi kapital. Kenaikan harga aset tersebut mendorong kenaikan kolateral sehingga semakin mendorong akumulasi kapital. Selama fase ekspansi, neraca perusahaan dan bank terlihat sehat sejalan karena kenaikan harga aset akan menutupi peningkatan pinjaman. Namun ketika optimisme tersebut berubah menjadi pesimisme, nilai aset akan terkoreksi yang menurunkan kekayaan bersih (net worth) perusahaan. Hal ini menimbulkan kesulitan keuangan perusahaan. Apalagi apabila bank kemudian merespons dengan memperketat kredit sejalan dengan memburuknya neraca perusahaan dan neraca bank. Kebijakan moneter mempunyai potensi dalam memitigasi risiko berkembangnya ketidak seimbangan di sektor keuangan. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian riil dan inflasi melalui pengaruhnya pada neraca perusahaan, neraca bank, dan perilaku perusahaan dan bank terhadap risiko. Oleh sebab itu, kebijakan moneter mempunyai peran yang signifikan dalam mempengaruhi ekspansi yang berlebihan di sektor keuangan yang mengarah kondisi yang tidak sustainable. Dengan demikian, kebijakan moneter memiliki potensi untuk mengurangi ketidakseimbangan di sektor keuangan dan prosiklikalitas dengan mengurangi optimisme yang berlebihan dan menekan permintaan kredit. Pentingnya kebijakan moneter dalam mengendalikan ketidakseimbangan di sektor keuangan, tidak berarti bahwa stabilitas harga aset menjadi target eksplisit kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri tidak mampu mengendalikan harga aset, terutama ketika spekulasi harga aset mendorong kenaikan harga aset yang menyebabkan imbal hasil dari aset tersebut sangat tinggi. Dalam kondisi demikian, perubahan suku bunga kebijakan tidak akan berpengaruh pada portofolio investor, terutama untuk investasi di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga kebijakan yang bersifat across the board ini akan menyebabkan overkill terhadap perekonomian secara keseluruhan. 340 Mengikuti prinsip Tinbergen bahwa satu instrumen tidak bisa digunakan untuk mentargetkan lebih dari tujuan, kebijakan moneter memerlukan instrumen tambahan untuk mendukungnya dalam mengendalikan kenaikan harga aset. Instrumen regulasi makroprudensial yang didisain untuk melakukan countercyclical dapat digunakan untuk mengatasi prosiklikalitas dan mendukung kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas makroekonomi (Gambar 2). Gambar 2. Kebijakan moneter dan makroprudensial dalam meredam prosiklikalitas Kebijakan Makroprudensial yang Countercyclical Konsep kebijakan makroprudensial Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individu. Walaupun kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial memiliki area yang saling tumpang tindih, kebijakan makroprudensial mempunyai tujuan dan peran tersendiri. Tujuan kebijakan moneter adalah menstabilkan harga dari barang dan jasa dalam perekonomian. Sementara 341 itu, tujuan dari kebijakan makroprudensial adalah untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka menjaga suplai jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus boom-bust suplai kredit dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas suplai intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output. Ada dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial. Pertama, dimensi cross-section, yang menggeser fokus dari regulasi prudensial yang diterapkan pada individual lembaga keuangan menuju pada regulasi sistem secara keseluruhan. Sejarah krisis keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari krisis keuangan yang terjadi di dunia bukanlah akibat dari masalah individual bank yang kemudian menular secara keseluruh sistem keuangan. Sebaliknya, krisis-krisis besar yang terjadi merupakan akibat dari eksposure terhadap ketidakseimbangan makro-keuangan yang dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar pelaku sistem keuangan. Oleh sebab itu, pandangan yang lebih holistik terhadap sistem keuangan dan hubungannya dengan perekonomian makro dari berbagai sisi sangat diperlukan. Dimensi kedua adalah dimensi time-series, yaitu kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menekan risiko terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dalam sistem keuangan.7 Dalam konteks ini, kebijakan makroprudensial harus didisain sedemikian sehingga mampu menghilangkan atau paling tidak memitigasi prosiklikalitas. Prinsipnya adalah bagaimana mendorong institusi keuangan untuk mempersiapkan bantalan (buffer) yang cukup di saat perekonomian sedang baik, yaitu ketika ketidakseimbangan dalam sistem keuangan umumnya terjadi, dan bagaimana menggunakan bantalan tersebut ketika perekonomian sedang memburuk. 7 Borio and Shim (2007) 342 Tujuan dari kebijakan makroprudensial yang bersifat countercyclical tersebut akan bersinergi dengan tujuan kebijakan moneter dalam mengurangi fluktuasi perekonomian. Kebijakan makroprudensial untuk memperketat persyaratan modal dan likuiditas di saat perekonomian sedang melaju kencang (periode upswing) akan mendorong bank untuk mengurangi pertumbuhan kredit sehingga menjaga daya tahan bank ke depan di saat perekonomian memburuk. Dalam kondisi demikian, upaya menjaga daya tahan sistem perbankan akan secara simultan mendukung tujuan kebijakan moneter untuk menstabilkan suplai kredit. Di saat krisis, ketika perekonomian dan harga aset anjlok, regulasi prudensial yang hanya berorientasi pada kesehatan individual bank akan mendorong bank memperketat pemberian kredit melalui kenaikan PPAP dan persyaratan modal yang lebih ketat. Mekanisme ini yang merupakan kritik banyak pihak terhadap Basel II. Basel II dimaksudkan untuk memperkuat manajemen risiko bank. Namun ia memiliki dampak prosiklikal karena kerangka Basel II secara tidak langsung mendorong bank untuk meningkatkan modal ketika perekonomian melemah, dan menurunkan modal ketika perekonomian sedang menguat. Pendekatan internal-rating based (IRB) dalam Basel II, persyaratan modal berbanding lurus dengan peluang terjadinya gagal bayar dan kerugian karena gagal bayar. Faktor-faktor risiko tersebut akan meningkat sejalan dengan memburuknya perekonomian. Ketika perekonomian melemah, kualitas debitur memburuk sehingga mengharuskan bank menyediakan tambahan modal. Karena menambah modal dalam jangka pendek tidak mudah, maka bank akan menurunkan penyaluran kredit untuk memenuhi ketentuan rasio modal. Dampaknya adalah perekonomian semakin mengalami kontraksi, risiko gagal bayar semakin meningkat dan modal bank semakin memburuk. Disinilah peran kebijakan makroprudensial yang akan menjamin aliran kredit dapat berlangsung secara kontinyu dengan mendorong bank mempersiapkan modal dan likuiditas di saat perekonomian sedang baik dan menurunkan persyaratan modal di saat krisis dan resesi sehingga tidak menghambat bank dalam penyaluran kredit. 343 Operasionalisasi Kebijakan Makroprudensial Secara operasional, sejumlah kajian telah dilakukan untuk mendisain kebijakan makroprudensial yang bersifat “countercyclical”.8 Basel III sebagai bagian dari upaya mengatasi prosiklikalitas dari Basel II telah menetapkan standar regulasi makroprudensial untuk permodalan baik dalam dimensi time series, sementara dimensi cross section sedang dalam pembahasan. Dalam dimensi cross section, lembaga keuangan yang tergolong dalam systemically important financial institutions (SIFIs) dikenakan kewajiban untuk menambah capital surcharge. Sementara itu, dalam dimensi timeseries, Basel III telah mengatur countercyclical buffer dengan diskresi nasional yaitu tambahan modal yang bersifat dinamis, yaitu meningkat ketika perekonomian sedang naik untuk mengerem pertumbuhan neraca bank dan turun ketika periode sedang melemah untuk memberikan insentif kepada bank untuk tetap menyalurkan kredit (Gambar 3). Hal yang krusial dalam regulasi ini adalah menentukan kapan tambahan modal diberlakukan. Salah satu pendekatan adalah dengan menggunakan sejumlah indikator yang dapat menggambarkan siklus kredit, seperti pertumbuhan kredit atau pergerakan rasio antara kredit terhadap PDB. Basel III menggunakan deviasi rasio kredit terhadap PDB terhadap trendnya berdasarkan argumen bahwa deviasi rasio kredit terhadap PDB secara empiris paling merepresentasikan pergerakan siklus finansial. Trend ini juga berfungsi menangkap perbedaan tahap perkembangan sektor keuangan (stage of financial development) antar negara. 8 Bank of England (2009), IMF (2009), dan Borio and Shim (2007). 344 Gambar 3. Ilustrasi countercyclical CAR Penyisihan penghapusan aktiva produktif (loan loss provision) juga bersifat prosiklikal. Pencadangan umumnya dilakukan ketika kelancaran membayar mulai terealisir atau dengan kata lain bersifat “backward-looking”, bukan ketika risiko mulai meningkat, namun ketika risiko mulai terjadi. Salah satu cara untuk menekan prosiklikalitas ini adalah mendorong bank melakukan pencadangan yang bersifat forward looking dengan model “dynamic provisioning” (Gambar 4). Model ini mendorong bank untuk membentuk cadangan pada saat kondisi perekonomian sedang baik dan menggunakannya pada saat perekonomian memburuk. Gambar 4. Ilustrasi dynamic provisioning 345 Arus modal asing juga bersifat prosiklikal.9 Arus modal masuk ke suatu negara terjadi ketika investor asing mempunyai ekspektasi akan membaiknya perekonomian domestik yang biasanya dibarengi oleh interest diferensial yang positif dan ekspektasi apresiasi dari mata uang domestik. Arus modal masuk ini apabila diintermediasikan ke sektor riil menimbulkan ‘credit boom’ yang mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, ketika terjadi ekspektasi terhadap perekonomian domestik memburuk terjadi arus modal keluar sehingga memperburuk perekonomian domestik. Langkah countercylical seperti akumulasi cadangan devisa pada saat arus masuk yang dapat dimanfaatkan sebagai self-insurance manakala terjadi arus balik. Namun langkah ini menyebabkan peningkatan likuiditas perekonomian sehingga memerlukan biaya sterilisasi yang tidak murah untuk penyerapannya. Kebijakan yang memberikan disinsentif bagi arus modal yang berjangka pendek, seperti Tobin-type tax, kewajiban hedging, dan persyaratan minimum-tinggal atas arus modal adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk memperpanjang jangka waktu arus modal masuk.10 Pengalaman dalam Implementasi Makroprudensial Penerapan makroprudensial sebenarnya bukanlah hal yang baru di Asia. Namun, implementasi regulasi makroprudensial lebih banyak dilakukan secara diskresi dan belum menjadi “built-in stabilizer”. Instrumen yang paling banyak digunakan adalah penyesuaian loan-to-value (LTV) ratio dan persyaratan modal, terutama bobot risiko dari CAR (Tabel 3). Dalam banyak kasus, penyesuaian-penyesuaian juga dilakukan bersamaan dengan instrumen yang ditujukan untuk pengendalian moneter, seperti giro wajib minimum dan pembatasan pinjaman pada sektor-sektor tertentu. Di Indonesia, instrumen yang sering digunakan adalah mengubah bobot risiko dari suatu jenis kredit, terutama untuk merespon terjadinya 9 Kaminsky, Reinhart, and Veigh (2004) dan Ocampo (2008). 10 Ocampo (2008). 346 “credit crunch” pascakrisis. Sebagai contoh, pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi relaksasi bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit setelah terjadi mini-crisis di akhir 2005. Di antara relaksasi regulasi tersebut adalah penyesuaian penurunan bobot risiko ATMR untuk kredit usaha kecil (KUK) menjadi 85%, kredit pemilikan rumah (KPR) 40%, dan kredit pegawai/atau pensiunan 50%. Pada tahun 2009, paska krisis 2008, Bank Indonesia juga kembali menurunkan bobot risiko aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Kredit UMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN dengan persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20% dan KUMKM yang dijamin bukan BUMN dari 85% menjadi sesuai rating lembaga penjamin tersebut. Tabel 3. Implementasi regulasi makroprudensial di sejumlah negara Instrumen x Penyesuaian bobot risiko dalam aturan permodalan (meningkatkan atau menurunkan bobot risiko) x Penerapan countercyclical provisioning (meningkatkan provisi untuk jenis kredit tertentu, eg. pinjaman ke debitur besar) Negara India, Indonesia, Malaysia, Croatia, Estonia, Irlandia, Portugal, Norway China, India x Pembatasan loan to value ratio (misalnya max 70%) China, Hongkong, Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Bulgaria, Norway, Portugal, Rumania x Pembatasan kredit ke sektorsektor tertentu (properti, kartu kredit) Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Hongkong, Thailand, Rumania x Perubahan reserve requirement China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Finland, Latvia, Estonia Sumber: Borio and Shim (2007), Hannoun (2010), Laporan Tahunan Bank Indonesia (beberapa tahun) 347 Regulasi makroprudensial lain yang diterapkan antara lain adalah penyesuaian GWM yang dikaitkan dengan LDR. Seperti halnya perubahan bobot risiko, penyesuaian GWM ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit. Sementara itu, untuk merespon peningkatan kredit yang tumbuh tinggi, biasanya Bank Indonesia hanya mengeluarkan moral suation. Pascakrisis, kebijakan makroprudensial lebih banyak dilakukan untuk mengelola arus modal, dengan tujuan agar arus modal masuk yang membanjir pascakrisis global tidak menimbulkan dampak negatif pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Dalam kaitan ini, beberapa kebijakan makroprudensial yang diterapkan antara lain seperti penetapan periode minimal kepemilikan protofolio domestik (holding period), regulasi pinjaman asing bank, penerapan GWM simpanan valuta asing (Tabel 4). Tabel 4. Kebijakan makroprudensial pascakrisis global Kebijakan Tujuan Minimum Holding Period pada SBI (1 bulan pada 2010 menjadi 6-bulan pada 2011) Mengurangi arus modal jangka pendek dalam bentuk SBI yang berisiko mengalami pembalikan. Memberlakukan kembali batas pinjaman asing bank Mengurangi arus modal jangka pendek yang diintermediasikan bank yang dapat meningkatkan eksposur bank terhadap risiko arus modal/nilai tukar. Meningkatkan GWM valas bank. 348 Memperkuat manajemen likuiditas valas bank sehingga meningkatkan ketahanan bank terhadap eksposur valas Meningkatkan GWM Rupiah bank menjadi 8% Menyerap likuiditas domesttik dan meningkatkan manajemen likuiditas bank. Memperpanjang jangka waktu SBI (3,6,9 bulan) Meningkatkan efektivitas pengelolaan likuditas domestik, termasuk yang bersumber dari arus modal masuk dengan menahannya dalam jangka yang lebih panjang. Kerangka Pengambilan Keputusan Dalam implementasi kebijakan makroprudensial, salah satu isu yang penting adalah apakah implementasinya akan menggunakan sebuah rule atau diskresi. Seperti halnya dalam kebijakan moneter, selalu ada trade-off antara menggunakan rule vs diskresi. Rule memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan kredibilitas kepada BI. Namun, rule yang terlalu kaku menutup fleksibilitas bagi BI untuk merespon perubahan-perubahan struktural maupun ketidakpastian yang sering terjadi dalam pasar keuangan. Sebaliknya, diskresi memberikan ruang gerak bagi BI untuk melihat dampak dari makroprudensial terhadap sistem keuangan dan perekonomian dan melakukan penyesuian-penyesuaian terhadap pendekatan yang digunakan dan melakukan judgment terhadap kebijakan yang akan diambil ke depan. Diskresi tentu saja menimbulkan ketidakpastian akan kebijakan ke depan yang diambil oleh BI. Ketidakpastian ini akan mendorong para pelaku pasar untuk cenderung ekstra hati-hati dengan menjaga tingkat likuiditas atau rasio modal melebihi dari yang diperlukan. Sebagai akibatnya, bank menjadi kurang efisien dan membebankan biaya modal tersebut kepada nasabah, menjadikan biaya kredit dalam perekonomian lebih mahal. Diskresi juga dapat mendorong terjadinya forbearence, terutama ketika dihadapkan suatu keputusan yang sulit atau tidak populer yang harus diambil. Apalagi, ketika keputusan diskresi tersebut mempunyai implikasi hukum terhadap bank sentral. 349 Mengingat adanya kelebihan dan kelemahan, baik dari rule maupun diskresi, model pengambilan keputusan diskresi terbatas11 (constrained discretion) sebagaimana halnya Inflation Targeting Framework (ITF) dapat menjadi alternatif terbaik. Dalam sistem ini, BI tetap harus mempunyai sebuah kerangka pengambilan keputusan yang jelas dengan sebuah rule yang ditentukan di awal. Rule yang diumumkan kepada publik ini menjadi patokan bank sentral dalam melakukan reaksi kebijakan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian, misalnya dalam bentuk persyaratan menambah modal atau menurunkan modal. Namun demikian, untuk menghindari kekakuan dari sistem ini, regulator tetap mempunyai opsi untuk secara diskresi menyimpang dari rule tersebut, misalnya, karena adanya shock di dalam perekonomian yang tidak dapat direspon dengan menggunakan rule yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan Taylor rule dalam kerangka ITF. Ketika tekanan inflasi diidentifikasi bersumber dari sisi suplai yang diperkirakan tidak memberikan dampak lanjutan kepada ekspektasi inflasi, bank sentral tidak harus merespon kenaikan inflasi di atas target sebagaimana telah ditentukan dalam Taylor rule. Namun demikian, pengecualian ini harus digunakan dalam situasi yang sangat jarang dan perlu dikomunikasikan secara jelas kepada pelaku pasar untuk menghindari masalah kredibilitas dari rule yang telah diumumkan serta agar mereka memahami mengapa regulor melakukan pengecualian tersebut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam isu rule vs diskresi ini adalah sistem hukum yang berlaku. Ketika sistem hukum masih lemah, seperti di Indonesia, dimana diskresi seringkali dipermasalahkan di depan hukum, maka akan lebih aman bagi regulator untuk menutup atau meminimalkan ruang diskresi. 11 Lihat Bank of England (2009) dan Libertucci dan Quagliariello (2010). 350 4. Menuju Paradigma Baru Kebijakan Moneter di Indonesia Dalam bab 3, telah didiskusikan bahwa kebijakan moneter memiliki potensi untuk mengendalikan berkembangnya ketidakseimbangan di sektor finansial. Namun instrumen suku bunga yang dimiliki harus didukung efektivitasnya dengan instrumen makoprudensial, khususnya untuk meredam prosiklikalitas sistem keuangan. Dalam konteks mengintegrasikan keduanya, isunya adalah bagaimana mengoperasionalkannya ke dalam kerangka kerja kebijakan moneter yang selama ini dianut, dalam kasus Indonesia adalah Inflation Targeting Framework. 5.1. Perubahan Paradigma Kebijakan Moneter Kerangka kebijakan moneter sebelum krisis global ditandai oleh tren penerapan inflation targeting framework (ITF) sebagai best practice kebijakan moneter yang banyak diterapkan, baik oleh negara maju maupun negara emerging.12 Praktek ini dilakukan sejalan dengan independensi bank sentral dengan mandat yang berfokus pada menjaga stabiltas harga. Di Indonesia, kerangka ITF telah diterapkan sejak tahun 2005. Dalam prakteknya, hampir semua bank sentral, termasuk Bank Indonesia, menerapkan apa yang disebut sebagai Flexible ITF, yaitu kebijakan moneter bukan saja ditujukan untuk mencapai target inflasi namun juga menjaga stabilitas output. Secara operasional, Flexible ITF menggunakan Taylortype rule sebagai benchmark rule, dimana suku bunga kebijakan merespon inflation gap – selisih antara proyeksi inflasi dan target inflasi, dan output gap – selisih antara proyeksi output dan output potensial. Inflasi dan output gap adalah variabel target, yaitu variabel yang masuk di dalam fungsi loss function bank sentral.13 Dalam kerangka ini, proyeksi inflasi dan perekonomian riil sangat tergantung pada pandangan bank sentral terhadap transmisi kebijakan moneter, asesmen perekonomian terkini, dan proyeksi variabel-variabel 12 Lihat Goodfriend (2007) yang menjelaskan konsensus kebijakan moneter sebelum krisis. 13 Fungsi loss function, Lt = (St - S*)2 + O(yt - y*)2 , dimana St adalah inflasi, S* target inflasi, yt - y* adalah output gap antara output, yt, dan output potensial, y*. 351 eksogen. Dalam kerangka ITF, kebijakan moneter seringkali diasumsikan ditransmisikan ke sektor riil dan inflasi melalui jalur suku bunga. Perubahan suku bunga kebijakan moneter akan direspon oleh suku bunga pasar, suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang kemudian berpengaruh pada permintaan agregat dan inflasi. Kondisi sektor keuangan, seperti kondisi pasar kredit dan harga aset hanya digunakan sebagai information variable, yaitu indikator untuk menjelaskan kondisi perekonomian (state of the economy). Variabel-variabel tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap respon suku bunga kebijakan yaitu melalui dampaknya pada proyeksi inflasi dan permintaan agregat. Tabel 5. Paradigma kebijakan moneter: Lama vs Baru Issues Peran kebijakan moneter Peran kebijakan makroprudensial dalam manajemen makroekonomi 352 Paradigma lama Paradigma baru Kebijakan moneter fokus pada kestabilan harga Kebijakan moneter ditujukan pada kestabilan harga, tetapi juga merespon ketidakseimbangan di sektor keuangan secara “simetris” Kebijakan makroprudensial tidak digunakan secara sistematis Kebijakan makroprudensial digunakan secara sistematis untuk memitigasi prosiklikalitas, untuk mendukung kebijakan moneter menjaga stabilitas makroekonomi. Jalur suku bunga sebagai transmisi utama kebijakan moneter Disamping interest rate channel, “balance sheet based channel” dan “risk taking channel” sangat berperan. Peran sektor keuangan dalam formulasi kebijakan moneter Hanya information variable Mempunyai peran sentral dalam menciptakan siklus bisnis. Mandat bank sentral Hanya pada stabilitas harga Stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan Kurang berperan Sebagai indikator dalam proses transmisi moneter dan berkembangnya risiko di sektor keuangan Transmisi kebijakan moneter Peran agregat moneter dan kredit Pertanyaannya kemudian adalah apakah kerangka flexible ITF cukup mampu mengatasi potensi tekanan terhadap stabilitas makroekonomi yang bersumber dari sektor keuangan. Inilah yang menjadi kunci pentingnya perubahan paradigma. Dalam paradigma baru, stabilitas harga berperan dalam stabilitas makroekonomi, namun stabilitas harga tidak cukup untuk menjamin tercapainya stabilitas makroekonomi. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2, sektor keuangan mempunyai peran sentral dalam menciptakan fluktuasi dalam perekonomian. Dalam paradigma ini, faktor finansial mempunyai peranan yang sangat krusial dalam mempengaruhi transmisi kebijakan moneter, baik melalui jalur neraca perusahaan, neraca bank, dan perilaku bank dan perusahaan dalam pengambilan risiko (risktaking channel). 353 Kerangka Flexible ITF dalam Paradigma Baru Implikasi penting dari paradigma baru terhadap kerangka kerja operasional ITF adalah perlu disain ITF yang fleksibel. Salah satu kelemahan dari ITF dalam hal kemampuannya menangani ketidakseimbangan di sektor keuangan adalah horizon kebijakannya yang terlalu pendek. Biasanya, di beberapa bank sentral horizon kebijakan adalah dua tahun. Di Indonesia, penetapan target dilakukan setiap tiga tahun dengan target tahunan, tanpa adanya rolling target. Artinya, dalam praktek, horizon target adalah satu tahun. Masalahnya, berkembangnya potensi risiko di sektor keuangan biasanya berlangsung dalam horison yang lebih panjang daripada horison sasaran inflasi. Mismatch ini menyebabkan kebijakan moneter yang konsisten untuk tujuan pencapaian inflasi bisa jadi tidak sejalan dengan pengendalian risiko di sektor keuangan. Kenaikan suku bunga BI rate di bulan Oktober 2008 sebagai respon kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan kenaikan harga komoditas di tengah krisis keuangan global yang berpotensi berdampak pada sistem keuangan Indonesia adalah kasus yang menarik perlunya horizon yang lebih panjang terutama ketika sistem keuangan dalam risiko. Permasalahan horison yang berbeda antara tujuan stabilitas harga dan finansial dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, memperpanjang horison pencapaian target inflasi untuk memberikan fleksibilitas pada kebijakan moneter untuk melakukan respon. Inggris, Swedia, dan Norway, sebagai contoh, memperpanjang horison sasaran inflasi dari dua tahun menjadi tiga tahun. Dalam konteks Indonesia, sasaran inflasi jangka panjang adalah 3%, sesuai dengan sasaran inflasi negara yang menerapkan ITF lainnya walaupun belum pernah diformalkan. Ke depan, sasaran jangka panjang ini perlu diformalkan oleh BI dan Pemerintah. Untuk sasaran jangka yang lebih pendek, katakanlah tiga tahun, perlu adanya ”rolling target” yang diumumkan setiap tahun yang mengarah pada target jangka panjangnya. Kedua, harga aset, khususnya harga rumah, dimasukkan ke dalam keranjang indeks harga konsumen (IHK) sehingga menginternalisir kenaikan harga aset. 354 Flexible ITF adalah salah satu strategi dalam menjembatani perbedaaan horison waktu untuk pencapaian stabilitas harga dan sistem keuangan. Namun, strategi ini tetap harus mempertimbangkan trade-off antara fleksibilitas dan kredibilitas. Dalam kaitan ini, perpanjangan horison waktu yang berlebihan dan dilakukan dengan sering akan mengurangi kredibilitas kebijakan itu sendiri. Penerapan Flexible ITF pada intinya dilakukan dengan menggunakan dua pilar, yaitu Pilar Kebijakan Moneter dan Pilar Kebijakan Makroprudensial. Instrumen utama dalam pilar moneter adalah suku bunga kebijakan BI rate, intervensi valas, dan instrumen pengeloalaan likuiditas. Kebijakan moneter merupakan instrumen utama dalam mempengaruhi suku bunga dan nilai tukar. Namun, seperti yang didiskusikan dalam Bab 4, instrumen suku bunga ini juga dapat digunakan untuk tujuan stabilitas sistem keuangan melalui pengaruhnya pada neraca perusahaan dan neraca bank. Kebijakan makroprudensial digunakan untuk mendukung kebijakan moneter melalui perannya secara langsung mempengaruhi neraca bank dan perusahaan dengan menggunakan instrumen makroprudensial, seperti surcharge CAR dan dynamic provision. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga inflasi yang rendah dan stabil dan juga mengurangi fluktuasi output. Sementara, tujuan akhir kebijakan makroprudensial adalah memitigasi prosiklikalitas yang berlebihan sehingga juga akan menekan fluktuasi output yang berlebihan. Dengan kerangka ini diharapkan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan dapat dicapai (Gambar 5). 355 Gambar 5. Kerangka Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Implikasi pada Mandat Institusional Bank Indonesia Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan pada mandat institusional Bank Indonesia. Paradigma bahwa kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial membawa konsekuensi bahwa tidak dapat dipisahkannya kedua kebijakan ini agar dapat berjalan secara efektif. Mandat yang dimiliki BI saat ini untuk menjaga stabilitas moneter dan pengawasan perbankan cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan makroprudensial, karena makroprudensial berada dalam dua spektrum fungsi makro (kebijakan moneter) dan fungsi mikro (pengawasan mikro perbankan). Namun, isu ini akan muncul manakala fungsi pengawasan perbankan dipisahkan dari BI dan diserahkan kepada lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila fungsi pengawasan perbankan dipisahkan dari Bank Indonesia, implementasi kebijakan makroprudensial ini menjadi lebih rumit. Dalam hal ini, kerangka kebijakan makroprudensial tidak bisa dihindari harus melibatkan dua institusi, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi mikro lembaga keuangan. Bank Indonesia mempunyai kemampuan melakukan asesmen 356 terhadap risiko makroekonomi dan perkembangan pasar keuangan global. Sementara itu, OJK mempunyai informasi tentang individual lembaga keuangan. Agar sistem berfungsi dengan baik, harus ada saling tukar menukar informasi antara BI dan OJK. OJK harus menyediakan semua informasi terkait dengan monitoring risiko individual, sebaliknya BI memiliki asesmen makroprudensial yang harus disampaikan kepada OJK agar dapat diimplementasikan pada level individu. Dalam konteks aliran informasi dan model koordinasi, Turner Review14 memberikan beberapa opsi yang dapat dijadikan rujukan. Pada intinya, bank sentral dengan kemampuan analisis di bidang makroekonomi dan sistem keuangan diberikan mandat untuk melakukan analisis makroprudensial, namun pada tataran implementasi ada sejumlah pilihan sebagaimana dalam Tabel 6. Opsi 2 adalah opsi yang ideal, dimana BI selain melakukan asesmen risiko, juga mengambil tindakan atau regulasi makroprudensial. Mengapa? Pertama, karena kebijakan yang bersifat makroprudensial perlu dukungan fungsi lender-of-last-resort yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Atas alasan ini, semua bank sentral di seluruh dunia mempunyai tanggung jawab untuk stabilitas sistem keuangan. Kedua, akuntabilitas akan lebih jelas apabila tanggungjawab diberikan pada sebuah lembaga. Opsi 3 adalah opsi yang paling sulit dilakukan, karena bentuk komite mempunyai risiko ketidakjelasan tanggungjawab dan akuntabilitas BI dan OJK, sehingga cenderung akan saling lempar tanggung jawab. Bagaimana dengan opsi 1? Opsi 1 dan opsi 2 lebih memiliki kejelasan tanggung jawab, apakah di BI atau OJK. Dalam memilih antara kedua model tersebut pertimbangan utamanya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan benturan kepentingan yang berpotensi timbul. Dalam opsi 1 terdapat potensi benturan kepentingan antara pengawasan individu (mikroprudensial) dan pengawasan makro (makroprudensial). Dalam kondisi tertentu, OJK mungkin menghadapi dilema dalam mencapai 14 The Turner Review: A regulatory response to the global banking crisis, March 2009 (www.fsa. gov.uk) 357 keduanya. Sebagai contoh, OJK akan lebih sulit untuk memperketat persyaratan modal ketika kredit sedang lari kencang (makro), apabila langkah tersebut menyebabkan ada beberapa individual bank yang mengalami kesulitan (mikro). Tabel 6. Disain institusional implementasi kebijakan makroprudensial dengan adanya OJK Asesmen Opsi Implementasi risiko Bank Indo- BI merekomendasikan ke OJK untuk melakuOpsi 1 nesia kan tindakan Opsi 2 Bank Indonesia BI mengambil tindakan atau memerintahkan OJK untuk melakukan tindakan. Opsi 3 Bank Indonesia ”Joint Commitee” (BI dan OJK atau FSSK) untuk mengambil keputusan akhir terkait dengan tindakan yang diambil Dalam opsi 2, potensi benturan kepentingan dapat juga muncul antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Namun, potensi ini dapat diselesaikan dengan memberikan instrumen regulasi prudensial pada bank sentral, disamping instrumen suku bunga untuk mengendalikan moneter. Dengan dua instrumen dan dua tujuan ini, sesuai dengan prinsip Tinbergen, kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara bersamaan. Implikasi pada Komunikasi Kebijakan Strategi komunikasi dalam konteks integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial merupakan hal yang sangat krusial, namun sekaligus sebuah tantangan yang tidak ringan. Pertama, menyampaikan “pesan” ke pasar tentang bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sesuatu yang sulit, karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. Respon kebijakan moneter terhadap ketidakseimbangan di sektor 358 keuangan melalui kenaikan suku bunga di tengah rendahnya tekanan inflasi secara ekonomi politik susah untuk diterima karena BI dapat dianggap tidak pro pertumbuhan dan kepentingan rakyat. Sebaliknya, komunikasi juga menjadi sebuah tantangan ketika terjadi tekanan inflasi terjadi pada saat prospek melemahnya pertumbuhan akibat memburuknya sektor keuangan. Oleh sebab itu, komunikasi yang persuasif kepada masyarakat tentang outlook yang lebih jangka panjang dan pentingnya menjaga stabilitas jangka yang lebih panjang sangat diperlukan. Strategi komunikasi untuk kondisi normal akan tidak bisa digunakan dalam kondisi optimisme yang berlebihan. Komunikasi kebijakan moneter perlu menyesuaikan dengan dinamika sistem keuangan yang sedang terjadi. Di sini, peran kebijakan makroprudensial yang bersifat rule-based dalam mendukung kebijakan moneter lebih mempermudah tugas BI. Dengan dukungan tersebut, kebijakan moneter hanya berperan dalam memberikan sinyal, daripada mengendalikan secara langsung berkembangnya risiko di sektor keuangan. Kedua, komunikasi kebijakan menjadi sangat menantang ketika terjadinya peningkatan ketidakpastian ekonomi ke depan sebagai hasil interaksi antara sektor keuangan, sektor riil dan perilaku pasar. Dalam konteks ketidakpastian ini, Goeltom (2010) memberikan beberapa prinsip. Pertama, pesan yang disampaikan harus dapat menjelaskan latar belakang kebijakan yang diambil BI sehingga pasar dapat memprediksi perilaku BI ke depan. Kedua, pesan juga harus dikemukakan bahwa pandangan BI terhadap outlook ke depan masih sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kebijakan BI ke depan sangat tergantung pada perkembangan kondisi perekonomian ke depan. 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan Krisis ekonomi global telah memberikan pelajaran berharga bagi otoritas moneter bahwa menjaga inflasi yang rendah tidaklah cukup untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi. Beberapa krisis yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa ketidakstabilan 359 makroekonomi lebih banyak bersumber dari sektor sistem keuangan. Sektor keuangan secara inheren menciptakan prosiklikalitas yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi. Oleh sebab itu, kunci dalam mengelola stabilitas makroekonomi bukan hanya bagaimana mengendalikan domestic imbalances (inflasi), external imbalances (neraca pembayaran), namun juga financial imbalances (pertumbuhan kredit, harga aset, perilaku risk-taking). Kenyataan ini membuka paradigma baru dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang memiliki tujuan utama menjaga stabilitas harga perlu bersinergi dengan kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lebih spesifik, kebijakan moneter berpotensi mendukung stabilitas sistem keuangan melalui kemampuannya mempengaruhi kondisi keuangan dan perilaku di pasar keuangan dalam mengambil risiko. Transmisi kebijakan moneter melalui balance sheet, bank lending, bank capital channel, serta risk-taking channel menjustifikasi peran kebijakan moneter untuk melakukan respon apabila terjadi potensi instabilitas yang disebabkan oleh sektor keuangan. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang didisain untuk memitigasi prosiklikalitas dalam perekonomian dapat mendukung kebijakan moneter dalam mengendalikan fluktuasi output dan inflasi. Paradigma ini memberikan sejumlah implikasi pada kerangka kebijakan moneter inflation targeting framework (ITF) yang diterapkan: x 360 ITF tetap relevan diterapkan sebagai kerangka kebijakan moneter. Namun, ITF perlu disesuaikan untuk mengakomodir stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, Flexible ITF dengan horizon yang lebih panjang memberikan ruang bagi kebijakan moneter untuk merespon berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan, terutama apabila ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan risiko sistemik yang menggangu perekonomian dan outlook inflasi. Namun, instrumen kebijakan moneter tidak perlu digunakan untuk merespon kenaikan asset bubble yang bukan bersumber dari kredit perbankan. Hal ini mengingat bahwa aset bubble biasanya ditandai oleh kenaikan imbal hasil yang berlebihan sehingga sulit dikendalikan hanya dengan kenaikan suku bunga kebijakan secara terbatas. Kenaikan suku bunga yang berlebihan secara across the board akan berdampak negatif pada sektor lainnya, seperti sektor UMKM. Oleh sebab itu, kenaikan asset bubble seharusnya diserahkan pada instrumen makroprudensial. x Paradigma baru ini memberikan implikasinya pada pendekatan analisis yang selama ini dilakukan dalam memformulasikan kebijakan moneter, termasuk model dan indikator yang digunakan. Modelmodel yang digunakan untuk proyeksi dan simulasi kebijakan perlu mengakomodir hubungan timbal-balik dan interaksi antara sektor keuangan dan sektor riil. Tidak adanya interaksi kedua sektor ini seringkali menyebabkan kebijakan moneter overlook terhadap apa yang terjadi di sektor keuangan, sehingga seringkali memandang rendah risiko di sektor keuangan pada saat ekspansi dan memandang berlebihan terhadap risiko pada saat kontraksi. x Karena balance sheet bank sangat berperan dalam proses transmisi kebijakan moneter, indikator kuantitas seperti kredit dan uang beredar mempunyai peran dalam formulasi kebijakan moneter, namun tidak berarti bahwa indikator-indikator tersebut menjadi ‘intermediate target’ karena inovasi keuangan dan integrasi keuangan secara global menyebabkan hubungan antara kuantitas uang dan perekonomian terus berubah. Kuantitas uang dan kredit ini lebih banyak berperan sebagai informasi dalam proses transmisi moneter dan risiko di sektor keuangan. Dalam sistem keuangan yang didominasi oleh perbankan, informasi mengenai kondisi perbankan seperti permintaan dan penawaran kredit, standar pemeberian kredit, delinquency ratio, dan NPL, maupun tingkat leverage debitur, sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. x Paradigma bahwa kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial membawa konsekuensi bahwa tidak dapat dipisahkannya kedua kebijakan ini dalam institusi yang berbeda agar dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, apabila fungsi 361 pengawasan perbankan dipisahkan dari Bank Indonesia, kerangka kebijakan makroprudensial tidak bisa dihindari harus melibatkan dua institusi, yaitu BI dan OJK. Jalan terbaik adalah BI diberikan mandat makroprudensial sedangkan OJK diberikan mandat mikroprudensial. Dalam konteks ini, BI berperan dalam melakukan asesmen risiko sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat melakukan regulasi dan tindakan yang dapat menyebabkan risiko sistemik. x 362 Terakhir, komunikasi kebijakan dalam paradigma terintegrasinya kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan menjadi lebih krusial. Respon kebijakan moneter terhadap berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan melalui kenaikan suku bunga sulit untuk diterima secara politik. Oleh sebab itu, komunikasi yang persuasif kepada masyarakat tentang outlook yang lebih berjangka panjang dan pentingnya menjaga stabilitas makro dan finansial dalam jangka panjang sangat diperlukan. Komunikasi ini semakin penting karena interaksi antara sektor keuangan dan sektor riil yang semakin kompleks dalam perekonomian yang semakin terintegrasi secara global semakin mengharuskan komunikasi yang intensif dengan pelaku pasar. Daftar Pustaka Agung, J, Kusmiarso,B, Pramono,B, Prasmuko, A, dan Prastowo (2001). Credit crunch di Indonesia setelah krisis : fakta, penyebab, dan implikasi kebijakan. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia. Bank of England (2009). The role of macroprudential policy: A Discussion Paper - November 2009. Bank Indonesia (2010). Laporan Perekonomian Indonesia 2009. Bank Indonesia Borio, C (2007b): “Monetary and prudential policies at a crossroads? New challenges in the new century”, Moneda y Crédito, 224, pp 63-101. Also available as BIS Working Papers, no 216, September 2006. Borio, C, C Furfine and P Lowe (2001): “Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options” in “Marrying the macro- and micro-prudential dimensions of financial stability”, BIS Papers, no 1, March, pp 1-57. Borio, C and P Lowe (2002): “Asset prices, financial and monetary stability: Exploring the nexus,” BIS Working Papers, no 114, July. Borio, C and I. Shim. (2007). What Can (Macro-) Prudential Policy do to Support Monetary Policy? (December 2007). BIS Working Paper No. 242. Borio, C and W White (2004): “Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes”, in Monetary policy and uncertainty: adapting to a changing economy, proceedings of symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, 28-30 August, pp 131-211. Also available as BIS Working Papers, no 147, February 2004. 363 Craig, R.S., Davis, E.P., Pascual A.G. (2006). Sources of Procyclicality in East Asian Financial System. In Procyclicality of Financial Systems in Asia. Edited by Stefan Gerlach and Paul Gruenwald. Palgrave Macmillan. Goodfriend, M. (2007). How the World Achieved Consensus on Monetary Policy, NBER Working Papers 13580, National Bureau of Economic Research, Cambridge-Massachusett. International Monetary Fund (2009). Lessons of the Global Crisis for Macroeconomic Policy. Febrary 2009. Kaminsky, G., Reinhart, C. and Vegh, C.A. (2004), When it Rains, it Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies (September 2004). NBER Working Paper No. W10780. Libertucci dan Quagliariello (2010). Rules vs Discretion in Macroprudential Policy. VOX: http://www.voxeu.org/index.php?q=taxonomy/ term/2176 Ocampo, J.A. (2008). Macroeconomic Vulnerability: Managing Pro-Cyclical Capital Flows. http://www.bot.or.th/English/EconomicConditions/Semina/Documents/09_Presentation_Ocampo.pdf The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, March 2009 (www.fsa.gov.uk). 364 PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA Bambang Brodjonegoro1 Andie Megantara2 I. Pendahuluan Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah tugas utama Pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan adalah melalui perumusan dan formulasi kebijakan fiskal yang prudent, sustainable, kredibel, dan transparan yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Secara historis, kebijakan fiskal sudah diterapkan di Indonesia sejak masa kemerdekaan sekitar tahun 1945. Tentu, model dan formula kebijakan fiskal yang ada pada masa itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Pasalnya, perumusan dan formulasi kebijakan fiskal pada suatu masa sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat itu baik dalam dimensi global maupun domestik dan diwarnai dengan karakteristik pemerintahan yang berkuasa di saat itu. Hal yang penting dicatat, setiap perjalanan kebijakan fiskal di Indonesia akan menggambarkan dinamika dan perkembangan ekonomi yang ada 1 2 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF 365 pada masa itu sekaligus menjadi catatan diri seberapa besar kemajuan kita jika dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Tentu, setiap pengalaman harus dijadikan pembelajaran berharga untuk melangkah semakin baik dan baik lagi. Dalam tulisan ini, disajikan perjalanan kebijakan fiskal di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini dengan titik momentum pada empat tahapan, yaitu: a. b. c. d. Kebijakan fiskal di masa orde lama (1945-1966) Kebijakan fiskal di masa orde baru (1966-1999) Kebijakan fiskal di masa krisis (1998-2008) Kebijakan fiskal terkini dan tantangan ke depan II. Kebijakan Fiskal di Masa Orde Lama Masa orde lama diawali saat pengakuan terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca perang kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Secara umum target pembangunan saat itu dititik beratkan pada pembangunan nasional (National Building) dan peran pemerintah dalam perekonomian sangatlah dominan. Pengeluaran pemerintah terkonsentrasi guna tujuan politik dan keamanan serta ketertiban, sehingga usaha untuk perbaikan di bidang ekonomi terabaikan. Pada masa itu anggaran pemerintah mengalami defisit. Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan pencetakan uang, yang kemudian mengakibatkan inflasi sangat tinggi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah serta kebutuhan pokok masyarakat sulit didapat. Kondisi ini diperparah dengan beredarnya berbagai jenis mata uang antara lain uang De Javasche Bank, uang pemerintah Belanda, uang NICA, ORI dan beberapa jenis uang lokal seperti URIPS-Sumatra, URITATapanuli, URPSU-Sumatra Utara/Aceh, URIBA-Aceh, URIDAP-Banten serta Uang Mandat-Pelembang. Secara teori dengan banyaknya jumlah uang yang beredar maka akan mempengaruhi kenaikan tingkat harga atau terjadinya inflasi. 366 Permasalahan lainnya adalah adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia yang baru merdeka, maka sangatlah mempengaruhi penerimaan atau kas negara. Di sisi lain eksploitasi besarbesaran di masa penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang juga mempengaruhi rendahnya sumber-sumber penerimaan negara. Memasuki tahun 1950, perkembangan kebijakan fiskal dan moneter saat itu antara lain pemerintah melakukan beberapa upaya pengendalian harga karena inflasi masih cukup tinggi. Disamping itu pemerintah melakukan perbaikan posisi neraca pembayaran serta penggalian sumbersumber pendapatan pemerintah guna menutup defisit anggarannya. Adapun langkah-langkah pemerintah yang diambil antara lain penyatuan mata uang. Langkah ini dilakukan De Javasche Bank (Bank Indonesia sekarang) dengan menerbitkan uang baru. Sedangkan ORI ditukar dengan uang baru berdasarkan daya belinya. Kebijakan yang cukup populer pada masa itu adalah kebijakan Gunting Syafrudin, yaitu pengguntingan uang kertas menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kiri dapat digunakan untuk bertransaksi, sedangkan sebelah kanan ditukar dengan obligasi pemerintah. Pada tahun 1957 saat dimulainya Ekonomi Terpimpin, perkembangan kebijakan fiskal ditandai dengan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali. Pengeluaran pemerintah ini banyak digunakan untuk operasi militer dan politik dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Upaya-upaya yang sangat penting saat itu antara lain mendorong perkembangan ekonomi pribumi dan perbaikan perusahaan hasil nasionalisasi. Pada tahun 1959 inflasi masih tinggi sehingga pemerintah melakukan penurunan nilai uang (Sanering). Pecahan Rp 5000 dan Rp1.000 masingmasing menjadi Rp50 dan Rp100. Giro dan deposito di atas Rp25.000 dibekukan dan diganti dengan pinjaman jangka panjang. Sedangkan kurs mata uang saat itu adalah US $ 1= Rp 45. Memasuki tahun 1960 proyek-proyek politis dan “mercu suar” pemerintah meningkat antara lain guna pembiayaan atas konfrontasi dengan 367 Malaysia, penyelenggaraan Asian Games, penyelenggaraan Pekan Olah Raga (GANEFO) serta pembebasan Irian Barat dari Belanda. Proyek-proyek ini mengakibatkan pengeluaran pemerintah sangat besar. Akhirnya pada tahun 1965, Bank Indonesia sebagai “Bank Berdjoang” bersedia menutupi defisit anggaran pemerintah dengan mencetak uang baru. Akibatnya inflasi sangat tinggi yaitu mencapai 635%. Pada bulan Desember 1965 terjadi penggantian uang, Rp1.000 uang lama diganti Rp1 uang baru. Dan akhirnya pada tahun 1966 terjadi krisis politik, yaitu pergantian pemerintahan Kabinet Ampera atau Orde Lama ke Orde Baru dan kebijakan fiskal pun berganti dengan berbagai masalah yang dihadapi antara lain beratnya pembayaran utang, defisit neraca pembayaran dan anggaran pemerintah, hiperinflasi yang mencapai 635% serta buruknya sarana dan prasarana ekonomi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan orde berikutnya yang sekaligus menjadi tantangan adalah rehabilitasi prasarana ekonomi, penyediaan bahan pangan terutama beras, peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim investasi terutama investasi asing dan pengendalian inflasi serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. III. Kebijakan Fiskal di Masa Orde Baru A. Formulasi Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal paling penting dalam masa orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto adalah pelaksanaan anggaran secara berimbang. Awal masa pemerintah orde baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto diawali dengan berbagai permasalahan dibidang ekonomi. Tingkat inflasi yang sangat tinggi (hyper inflation), defisit neraca perdagangan, tingginya beban utang luar negeri, defisit anggaran dan buruknya kondisi perekonomian; menjadi problem besar yang harus segera diatasi. Beberapa kebijakan pengelolaan ekonomi yang ditempuh awal pemerintahan orde baru adalah : (1) Membangun kembali infrastruktur ekonomi yang rusak (jalan, pelabuhan, listrik, irigasi); (2) Pengendalian 368 inflasi melalui kebijakan “balances budget” atau APBN seimbang dengan cara menutup defisit anggaran melalui pinjaman luar negeri; (3) Membuka kembali keran ekonomi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); (4) Pencukupan kebutuhan pangan, dengan menggabungkan kebijakan produksi dengan harga dan operasi cadangan (buffer stock operation); (5) Pencukupan kebutuhan sandang. Pada APBN 1967 terjadi defisit sebesar Rp 2,66 miliar rupiah atau 3 persen dari total pengeluaran Negara yang besarnya Rp 87,55 miliar. Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam menurunkan laju inflasi, pemerintah orde baru mulai menerapkan Anggaran berimbang (balanced budget). Kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis terutama ditujukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan, sehingga Tabungan Pemerintah dapat terhimpun dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Usaha untuk itu antara lain dilakukan melalui peningkatan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan bukan minyak. Strategi penerapan anggaran berimbang berhasil mengendalikan inflasi. Defisit APBN ditutup dengan hutang luar negeri, tanpa disertai pencetakan uang baru seperti yang terjadi pada masa pemerintahan orde lama. Laju inflasi pada tahun 1966 yang mencapai 637 persen setahun atau 53 persen rata-rata per bulan, turun drastis menjadi 112 persen pada tahun 1967. Penurunan laju inflasi terus berlanjut, pada tahun 1968 sebesar 79 persen, dan tahun 1969 turun lagi menjadi hanya 11 persen. Dalam memenuhi kecukupan pangan masyarakat, pemerintah orde baru terus berusaha menekan harga beras. Upaya dilakukan dengan peningkatan produksi melalui pengadaan penyediaan pupuk dan insektisida, penemuan bibit unggul PB-5 dan PB-8 serta penyuluhan pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan pasokan beras, juga dilakukan kebijakan import untuk menutupi kebutuhan beras jangka pendek. Di samping itu Pemerintah telah pula menempuh kebijaksanaan harga pembelian beras. Kebijakan ini dilakukan dapat meningkatkan daya beli para petani sehingga 369 dapat meningkatkan gairah para petani untuk meningkatkan produksi padi. Dengan bermodalkan hasil-hasil stabilisasi dan rehabilitasi yang telah dicapai selama dua tahun masa pemerintahan orde baru, untuk menciptakan suatu landasan yang kokoh serta iklim yang sehat dalam melancarkan usaha-usaha pembangunan, tahun anggaran 1969-1970 ditetapkan sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). REPELITA bertujuan sebagai rencana tahapan dalam pendapatan nasional dan pendapatan per kapita serta memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. APBN merupakan alat untuk melaksanakan program-program pembangunan secara berkelanjutan, yang telah dijabarkan dalam REPELITA. Dari sisi perpajakan, Pemerintahan orde baru melakukan reformasi sistem pajak pada tahun 1967. DPR mengesahkan perubahan UndangUndang yang terkait dengan metode pengenaan pajak. Dengan sistem pembayaran pajak yang baru, pembayar pajak memiliki dua cara dalam membayar pajak. Metode pertama adalah menghitung sendiri kewajiban pajak individu yang harus dibayar. Dengan menggunakan metode ini, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar dan menyerahkan pajak ke kantor pajak. Metode kedua adalah penghitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak. Dengan sistem ini beban petugas pajak dalam menghitung pajak menjadi berkurang, dan masyarakat diberikan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Reformasi perpajakan pada masa pemerintah orde baru terjadi lagi pada tahun 1983 dengan diundangkannya 3 (tiga) ketentuan perpajakan yaitu: UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN/PPnBM. Tujuan utama reformasi perpajakan ini untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan kerumitan dari perpajakan. Dengan stabilitas politik dan keamanan yang semakin mantap, pemerintah orde baru mulai mengundang investor baik domestik maupun 370 asing untuk menanamkan modalnya. Sadar akan potensi sumber daya tanah air yang belum mampu diolah karena keterbatasan modal, pengalaman dan teknologi, disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), serta Undang-Undang Nomor 6 tahun tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bantuan dari negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) mulai mengalir, dan dilanjutkan oleh CGI (Consultative Group on Indonesia) yang diketuai oleh Bank Dunia mampu menggerakan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. B. Kebijakan Perbankan Kebijakan ekonomi pemerintahan orde baru memasuki babak penting dengan dikeluarkannya deregulasi perbankan pada tahun 1983. Melalui kebijakan deregulasi perbankan ini, pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) tidak lagi campur tangan dalam penentuan suku bunga bank, tetapi penentuan suku bunga sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, suku bunga bank-bank pemerintah diatur oleh bank sentral. Kewenangan penyaluran alokasi kredit pada sektor-sektor prioritas dalam pembangunan yang disalurkan melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), menjadi kewenangan bank sentral. Kebijakan tersebut ditujukan untuk merangsang investasi. Kebijakan moneter dengan menekan suku bunga bank pemerintah lebih rendah dibanding tingkat bunga pasar (bank-bank swasta) akan menekan jumlah tabungan masyarakat di lembaga perbankan. Rendahnya suku bunga riil (suku bunga nominal dikurangi inflasi) yang rendah tidak mendorong masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan (melalui kredit bank) menjadi tidak optimal. Kebijakan suku bunga rendah yang semula dimaksudkan untuk merangsang investasi, dalam kenyataannya bisa terhambat karena kelangkaan dana investasi itu sendiri. Oleh karena itu kebijakan deregulasi perbankan yang dikeluarkan melalui paket kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 1983) merupakan tonggak 371 penting dalam sejarah kebijakan ekonomi orde baru karena pemerintah melepaskan kendali dalam penentuan suku bunga bank kepada mekanisme pasar. Dampak nyata adalah meningkatnya suku bunga perbankan, karena setiap bank dipaksa untuk bersaing dalam memperebutkan dana masyarakat yang terbatas. Persaingan tersebut semakin ketat dengan dikelurkannya kebijakan liberalisasi perbankan melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Melalui kebijakan ini pemerintah memperlonggar “barriers to entry” dengan cara memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi sektor swasta nasional untuk mendirikan bank baru atau memperluas cabangnya di tanah air. Bank asing pun diberikan keleluasaan membuka kantor cabangnya di luar ibukota. Dampak langsung dari PAKTO 1988 adalah semakin banyaknya jumlah bank nasional maupun kantor-kantor cabang bank asing di kota-kota besar. C. Kebijakan Hutang luar negeri Perkembangan pinjaman luar negeri Indonesia mengalami peningkatan cukup tinggi sejak tahun 1993 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Pinjaman pada tahun 1993 sebesar USD 80,6 miliar, meningkat menjadi USD 150,9 miliar pada tahun 1998. Akibat dari besarnya utang luar negeri sektor swasta yang berjangka waktu pendek, mengakibatkan permintaan terhadap valuta asing meningkat tajam, sementara cadangan devisa nasional pada saat itu hanya sekitar USD 15 miliar. Kurs mengalami tekanan berat dan anjlok dari Rp2.300 pada tahun 1996, menjadi Rp16.725 per USD pada Juni 1998. Rekomendasi IMF dalam “Letter of Intent (LoI) ” agar pemerintah melakukan penutupan terhadap 16 bank pada Nopember 1997 dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap bank, ternyata malah menyebabkan kepanikan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (rush). Anjloknya nilai tukar rupiah menutup masa pemerintahan orde baru dengan menyisakan hutang luar negeri dan dalam negeri yang sangat besar. 372 IV. Kebijakan Fiskal di Masa Krisis Seiring waktu berjalan, tahun 1997/1998 dunia dihadapkan pada krisis ekonomi global. Berbagai negara termasuk Indonesia merasakan betapa dahsyatnya dampak krisis global tahun 1997/1998 kala itu. Pada awalnya, transformasi krisis global ke Indonesia ditandai dengan guncangan dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap US$. Tingkat depresiasi rupiah semakin lama semakin dalam. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap US$ yang pada bulan tahun 1996 masih sekitar Rp2.328, sejak awal tahun 1997 terus mengalami pelemahan di sepanjang tahun 1997 dan pada akhir tahun di tutup pada level Rp4.827 per US$. Kemudian, dalam tahun 1998 pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ semakin dalam dan pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap US$ dalam tahun 1998 berada di kisaran Rp9.929. Ini maknanya, dalam periode 1996 hingga 1998 rupiah mengalami depresiasi sekitar 326,50 persen terhadap US$. Hal ini pada gilirannya tentu berdampak tidak baik terhadap sektor fiskal dan kondisi perekonomian pada umumnya. Selain nilai tukar, implikasi krisis ekonomi global terhadap pasar Indonesia juga bisa diidentifikasi dari gejolak di lantai bursa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada akhir tahun 1996 ditutup pada level 637.43, di paruh pertama tahun 1997 masih terus bergerak naik dan mencapai titik 740.83 pada tanggal 8 Juli 1997. Namun, setelah periode itu cenderung terus mengalami pelemahan hingga ditutup pada level 401.71 di akhir tahun 1997. Di tahun 1998 seiring semakin membesarnya intensitas krisis, IHSG juga terus melemah dan pernah menyentuh level 256.83 pada tanggal 21 September 1998. Ini merupakan dampak nyata dari krisis global yang berimbas pada terjadinya pelarian modal asing (capital outflow) dari pasar finansial Indonesia. Penting dicatat bahwa fenomena pelemahan indeks saham saat itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di kawasan regional dan negara-negara lainnya sebagai dampak capital outflow dalam rangka pembiayaan likuiditas global. Untuk menghindari terjadinya capital outflow secara lebih dalam, Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan moneter ketat (tight monetary 373 policy) dengan terus menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tercatat, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan yang pada awal tahun 1997 masih sebesar 12,15 persen, pada pertengahan tahun 1998 sudah jauh melambung mencapai 70,81 persen. Selanjutnya, kenaikan suku bunga SBI 1 bulan tersebut memicu peningkatan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga perbankan lainnya baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga kredit. Seiring waktu berjalan, krisis ekonomi tahun 1998 semakin lama semakin meluas dan berkembang menjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif kala itu, berhembus rumor yang kurang sedap di bidang perbankan yang mengikis kepercayaan masyarakat yaitu rumor yang mengatakan bahwa banyak bank yang kalah kliring atau rugi besar-besaran akibat transaksi valas dan akan ada pemilik bank yang kabur ke luar negeri. Kondisi demikian, semakin memperparah keadaan saat itu. Implikasinya, terjadi bank run atau penarikan dana simpanan secara besar-besaran di perbankan nasional. Melihat kenyataan ini, Pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah dan upaya recovery terus ditempuh. Salah satunya adalah dengan membuka kran kerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Sebagai konsekuensi dari kontrak kerja sama ini, Pemerintah beberapa kali menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan lembaga keuangan internasional tersebut. Namun, asistensi Tim IMF di Indonesia sepertinya tidak berjalan mulus dan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dari berbagai diskursus yang ada saat itu baik oleh lembaga ekonomi, pengamat ekonomi maupun kalangan akademisi, berkesimpulan bahwa langkah-langkah yang dianjurkan IMF tidak bekerja efektif dan justru hanya meningkatkan akumulasi utang Indonesia. Selain itu, formulasi IMF dalam penyehatan perbankan nasional dianggap justru keliru dan dilakukan tanpa skenario yang jelas sehingga hanya berujung pada likuidasi 16 bank nasional. Selanjutnya, hal ini menjadi trigger terjadinya rush atau penarikan dana secara massal pada perbankan yang juga mencerminkan penurunan tingkat kepercayaan 374 masyarakat terhadap Pemerintah khususnya perbankan. Situasi demikian jelas tidak sehat bagi perekonomian. Setelah mencermati berbagai perkembangan terkini baik ekonomi dan keuangan serta dengan memperhatikan berbagai masukan yang ada, Pemerintah akhirnya pada tahun 2003 mengambil langkah Post-Program Monitoring dan memutuskan mengakhiri kerja sama dengan IMF dan percaya pada kemampuan sendiri. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi berbagai kebijakan baik kebijakan fiskal, kebijakan di sektor finansial, maupun kebijakan moneter dalam rangka pemulihan pascakrisis ekonomi global 1997/1998. Dari perspektif fiskal, beberapa kebijakan fiskal yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka masa recovery dari krisis global diantaranya : a. Melaksanakan reformasi fiskal secara menyeluruh; b. Mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin dan efisiensi fiskal; c. Menurunkan subsidi; d. Mengurangi utang luar negeri dan mengkonversikannya menjadi utang domestik; e. Melakukan reschedulling atas utang-utang luar negeri yang jatuh tempo pada saat itu; f. Meningkatan penerimaan pajak secara terus menerus dan konsisten; g. Melakukan penghematan dan penajaman dalam fungsi belanja negara; h. Mereformulasi dan merestrukturisasi sistem anggaran negara. Pemulihan dampak krisis melalui berbagai pendekatan – yang didukung dengan kerja keras Pemerintah dan bantuan semua pihak – akhirnya membuahkan hasil. Setelah berkontraksi cukup tajam pada level 13,13 persen di tahun 1998, kinerja ekonomi kembali mampu berekspansi sejak tahun 1999. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1999 hingga saat ini mempunyai kecenderungan semakin baik dan semakin meningkat. 375 Bagaikan suatu siklus, krisis memang selalu berulang. Berselang sepuluh tahun sejak krisis global 1997/1998, di pertengahan tahun 2008 dunia khususnya kawasan Asia kembali dilanda krisis. Dampaknya, berbagai negara tak terkecuali Indonesia merasakan imbas krisis 1998 tersebut. Namun demikian, dampak krisis tahun 2008 tidak sedahsyat krisis sepuluh tahun sebelumnya. Ada dua faktor penjelas untuk hal ini, yaitu: (1) Secara magnitude, kondisi krisis 2008 memang tidak sebesar krisis tahun 2008 baik dari variabel penyebab krisis maupun negara-negara yang terkena dampak langsung krisis dan (2) Secara fundamental, Indonesia pada tahun 2008 jauh lebih siap dalam menghadapi dan menanggulangi krisis ekonomi dibandingkan kondisi sepuluh tahun silam. Hal ini dikarenakan seiring waktu berjalan Indonesia telah menyiapkan sejumlah instrumen proteksi sebagaimana tertuang dalam Crisis Management Protocol baik dari sisi fiskal maupun finansial. Terkait dengan Crisis Management Protocol, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua tahap, yakni pre-emptive policy atau tahap pencegahan dan executing policy atau tahap penanganan. Perlu ditekankan bahwa upaya yang dijalankan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam penyelesaian krisis tahun 2008 sebenarnya masih sebatas pre- emptive policiy. Ini mengingat, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring secara periodik dan persisten yang dilakukan terhadap perkembangan sejumlah indikator ekonomi terkini, Pemerintah dan BI saat itu berkesimpulan bahwa kondisi turbulensi saat itu belum masuk pada tatanan krisis. Untuk menyatakan negara dalam kondisi krisis, Pemerintah dan BI akan menetapkannya dalam suatu surat keputusan. Sehubungan hal tersebut di atas, langkah dan upaya yang ditempuh pun juga masih sebatas pada penangkalan dan pencegahan krisis dengan tujuan untuk menstabilkan kondisi pasar finansial dan memulihkan kepercayaan masyarakat akibat gejolak-gejolak eksternal yang bersifat sementara (temporary shocks). Adanya stabilitas pasar finansial dan pemulihan kepercayaan menjadi begitu penting untuk menghindari terjadinya bank run dan systemic insolvency sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1998 lalu. 376 Dari sisi regulator, skenario penanganan krisis 2008 bisa dibedakan dari dua perspektif yakni Pemerintah dan BI. Dari sisi Pemerintah, sebagai bentuk keseriusan dalam pencegahan krisis, Pemerintah telah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), yakni Perpu nomor 2 tahun 2008 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia; Perpu nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Selain menerbitkan tiga Perpu, dalam level mikro Pemerintah juga telah menempuh beberapa langkah strategis seperti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2008 tentang peningkatan nilai penjaminan nasabah di perbankan hingga dua puluh kali lipat, yakni dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar. Hal ini penting untuk meningkatkan ketenangan deposan dan menghindari bank run. Sedangkan, dalam rangka mereduksi volatilitas pasar, Pemerintah juga menyetujui aturan baru otoritas bursa yang melakukan adjusment terhadap batasan auto rejection yakni menjadi 20 persen untuk batas atas dan 10 persen untuk batas bawah. Kemudian, untuk memulihkan kepercayaan pasar dan stabilisasi harga saham-saham BUMN, Pemerintah mencadangkan dana sekitar Rp4 triliun yang ditempatkan pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Perusahan Pengelola Aset untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham-saham BUMN yang berkinerja bagus dan Pemerintah melakukan penjajakan kerja sama dengan Bank Dunia melalui skema Credit Line dan Stand By Loan senilai US$2 miliar. Sementara, dari sisi sektor riil, untuk mendorong ekspansi ekonomi, Pemerintah juga mengupayakan terjadinya akselerasi pencairan APBN melalui berbagai insentif dan disinsentif pada sejumlah instrumen fiskal. Saat itu, Pemerintah dan BI juga mengupayakan berbagai langkah hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana dengan menebarkan rumor negatif untuk kepentingan pribadi. Lebih jauh, dalam Pasal 23 Undang-Undang (UU) 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 juga diakomodasi payung hukum untuk mengantisipasi 377 keadaan darurat sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terjadi keadaan darurat seperti: (a) penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; (b) kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan; dan (c) krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), maka Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 1 X 24 jam, bisa melakukan langkah-langkah berikut: 1. Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2009; 2. Pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu kementerian negara/lembaga dan/atau antar kementerian negara/lembaga; 3. Penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/ kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai; 4. Penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral maupun multilateral; dan 5. Penerbitan SBN melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan; Penting dicatat bahwa substansi pasal 23 UU 41 Tahun 2008 pada dasarnya menjadi panduan dalam menjalankan protokol penanggulangan krisis dari dimensi kebijakan fiskal. Penanggulangan krisis memang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dari sisi kebijakan fiskal agar tidak menyebar secara luas dan berdampak kemana-mana. Tentunya, penanganan kebijakan fiskal secara cepat dan tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai prosedur dan payung hukum yang berlaku. 378 A. Stimulus Fiskal 2009 Pada tahun 2008, Indonesia memang relatif aman dari dampak krisis ekonomi global. Meskipun terkena imbas, namun dampaknya masih dalam level moderat dan bisa diantisipasi dengan baik. Dalam tahun 2009, krisis diperkirakan belum sepenuhnya pulih dan masih bisa berlanjut sebagaimana diproyeksikan beberapa lembaga ekonomi internasional. Dana moneter internasional atau IMF misalnya, dalam laporan terbarunya bulan Nopember 2008, memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 2,2 persen pada 2009. Sedangkan, Consensus Forecasts dalam edisinya bulan Nopember 2008 juga memperkirakan laju PDB riil dunia tahun 2009 hanya sekitar 1,1 persen. Sementara, OECD dalam Outlook-nya terbaru, memperkirakan laju PDB riil negara-negara utama dunia seperti AS, Japan, dan Zona Eropa sepanjang 2009 akan mengalami kontraksi dari kisaran 0,3 persen hingga 2,0 persen. Untuk mengantisipasi berlanjutnya krisis di tahun 2009 tersebut sekaligus meningkatkan proteksi terhadap masyarakat luas dan dunia usaha, Pemerintah melalui persetujuan DPR memutuskan mengucurkan stimulus fiskal pada tahun 2009. Tentunya, pengucuran stimulus fiskal berorientasi untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak langsung krisis global sekaligus untuk menghindari terjadinya gelombang rasionalisasi secara massal. Secara teknis, stimulus fiskal tahun 2009 dikucurkan melalui dua jalur, yakni pemberian subsidi kepada barang-barang tertentu misalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian insentif pajak. Pada tahun 2009, besaran subsidi yang dikucurkan mencapai Rp166,70 triliun yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp103,57 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp63.13 triliun. Sedangkan, terkait insentif pajak, bisa dijelaskan bahwa pada prinsipnya, payung hukum pemberian insentif kepada masyarakat khususnya dunia usaha diberikan melalui amandemen terhadap tiga undang-undang perpajakan, yakni: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). 379 Hingga akhir 2008, Pemerintah dan DPR telah merampungkan amandemen terhadap UU KUP, yang ditandai dengan lahirnya UU KUP baru yakni UU Nomor 28 Tahun 2007. Sedangkan, untuk UU PPh juga ditandai dengan lahirnya UU PPh baru Nomor 36 Tahun 2008. Sementara, amandemen terhadap UU PPN dan PPnBM masih dalam proses pembahasan dengan DPR. V. Harga Minyak dan Inflasi: Tantangan Kebijakan Fiskal ke Depan A. Kebijakan Fiskal dan Harga Minyak Pergerakan harga minyak mentah sangat berfluktuasi sehingga sangat sulit untuk memperkirakan harga minyak kedepan. Selain faktor fundamental seperti permintaan dan penawaran, fluktuasi harga minyak juga dipengaruhi oleh faktor nonfundamental seperti spekulasi dan krisis geopolitik. Oleh karena itu, terdapat faktor risiko yang perlu diwaspadai terkait dengan harga minyak ke depan. Risiko fiskal yang berasal dari kenaikan harga minyak ditransmisikan secara langsung melalui dua sisi pada APBN. Sisi penerimaan melalui kenaikan penerimaan PPh Migas, PNBP migas maupun penerimaan yang berasal dari Domestic Market Obligation (DMO) minyak, serta sisi pengeluaran melalui peningkatan subsidi BBM, Subsidi Listrik dan transfer Dana Bagi Hasil ke daerah serta anggaran pendidikan. Realisasi belanja subsidi pada tahun 2010 yang mencakup subsidi energi dan subsidi non-energi mencapai Rp214,2 triliun atau 55,1 persen lebih tinggi dari realisasi 2009. Realisasi subsidi BBM 2010 mencapai Rp82,4 triliun atau meningkat 82,8 persen dari realisasi 2009. Hal ini disebabkan oleh tingginya realisasi harga ICP di pasar internasional yang mencapai rata-rata (Januari-Desember) US$79,4/barel, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2009 yang mencapai US$61,6/barel. Selain itu, membengkaknya subsidi BBM juga disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) pada tahun 2010, lebih tinggi dari realisasi 2009 yang mencapai 37,9 juta 380 kl. Selanjutnya, kenaikan harga minyak mentah juga turut mendorong peningkatan subsidi listrik hingga mencapai Rp57,6 triliun pada tahun 2010 atau meningkat 16,3 persen dari realisasi 2009. Selain disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah, peningkatan subsidi listrik tersebut juga diakibatkan oleh penambahan konsumsi BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik karena terhambatnya pasokan gas dan batubara. Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan triwulan I 2011 mencapai Rp32,4 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama didominasi oleh realisasi subsidi energi yang mencapai Rp24,8 triliun atau 18,1 persen dari pagu. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi subsidi tahun 2011, antara lain: (i) tingginya realisasi harga ICP yang rata-rata sebesar US$104,5/barel selama triwulan I 2011, lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar US$80/ barel; (ii) meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi selama triwulan I 2011 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; (iii) adanya perubahan komposisi energi input pembangkit PT PLN (Persero) sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan bahan bakar minyak sebagai konsekuensi tidak tercapainya pasokan gas; dan (iv) kebijakan pencairan subsidi pangan lebih awal untuk mengurangi beban biaya. 381 Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Sumber : Kementerian ESDM, data diolah Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan peningkatan subsidi BBM adalah melakukan pengaturan distribusi BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut sedianya akan dilaksanakan pada 1 April 2011, namun hingga saat ini masih ditunda. Hal ini dikarenakan harga minyak mentah masih sangat tinggi sehingga perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi akan sangat lebar. Penundaan tersebut memberikan waktu lebih banyak bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Selain kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, beberapa langkah yang akan dilaksanakan untuk mengendalikan besaran subsidi adalah: (i) penataan ulang pola pendistribusian BBM melalui pengurangan jumlah dispenser dan pasokan BBM bersubsidi di kawasan elit dan tertentu lainnya; 382 (ii) memperbanyak jumlah dispenser dan pasokan BBM nonsubsidi; (iii) meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi; (iv) melanjutkan konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG); dan (v) melakukan sosialisasi dan kampanye hemat BBM. Sementara itu, kebijakan yang terkait dengan pengendalian anggaran subsidi listrik tahun 2011 dilakukan melalui efisiensi internal PT PLN dan penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tenaga Listrik. Upaya penurunan BPP tersebut dilakukan melalui program peningkatan efisiensi dengan cara optimalisasi pembangkit tenaga listrik dan penurunan susut jaringan (losses), diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik melalui optimalisasi penggunaan gas, peningkatan penggunaan batubara dan panas bumi. Namun demikian, upaya penurunan BPP Tenaga Listrik tersebut di atas mengalami beberapa kendala, antara lain: (i) keterlambatan beroperasinya beberapa proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I; (ii) tidak terpenuhinya kebutuhan gas sesuai kontrak yang mengakibatkan naiknya volume BBM untuk mensubstitusi kekurangan pasokan gas; dan (iii) adanya kenaikan penggunaan BBM pada beberapa pembangkit listrik untuk mengatasi pemadaman di beberapa wilayah. Realisasi defisit APBN 2011 diperkirakan akan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2011. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah perkembangan harga minyak mentah terkini yang jauh melampaui asumsi APBN 2011. Selain itu, implementasi kebijakan yang telah direncanakan dan kebutuhan belanja yang meningkat juga mempengaruhi peningkatan defisit pada APBN 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan melampaui rencana APBN, dengan didukung peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP. Perkiraan peningkatan penerimaan perpajakan di tahun 2011 didukung dari penerimaan pajak perdagangan internasional yang diperkirakan akan jauh melampaui target APBN 2011 karena meningkatnya aktivitas perdagangan dunia dan tingginya harga CPO di pasar internasional. Di bidang PNBP, kecenderungan kenaikan harga minyak diperkirakan akan membawa dampak positif bagi penerimaan migas. 383 Alokasi subsidi di tahun 2012 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berarti, seperti adanya kecenderungan harga minyak internasional yang sulit diprediksi akibat kondisi geopolitik dunia internasional yang tidak menentu. Selain itu, masih tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi terkait implementasi pelaksanaan program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di tahun 2011 dan mendatang. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan mempunyai dampak yang luas pada pembangunan nasional, diantaranya: (i) memenuhi rasa keadilan, karena subsidi hanya akan diterima oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi; (ii) mengingatkan masyarakat untuk menghemat pemakaian energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable energy); (iii) mendukung ketahanan energi nasional jangka panjang; (iv) mengurangi dampak perubahan iklim; (v) mengalihkan efisiensi anggaran ke belanja yang lebih produktif dan bermanfaat maksimal pada pembangunan dan masyarakat; (vi) mengurangi beban kemacetan lalu lintas yang berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi dan APBN. Guna mencapai anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran di tahun 2012, maka subsidi listrik harus diturunkan dengan upaya penurunan konsumsi BBM oleh PT PLN dari total biaya bahan bakar. Oleh karena itu, subsidi listrik di tahun 2012 masih menghadapi tantangan berkaitan dengan ketidakpastian pasokan gas dan batubara serta fluktuasi harga komponen bahan bakar pembangkit. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua, sehingga penggunaan BBM masih tinggi. B. Kebijakan Fiskal untuk Pengendalian Inflasi Tahun 2010, laju inflasi meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari pemantauan BPS di 66 kota, sampai akhir tahun 2010 tercatat laju inflasi kumulatif mencapai 6,96 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,78 persen. Namun, inflasi tahun 2010 tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 11,06 persen. 384 Potensi tekanan inflasi tahun 2011 diperkirakan masih bersumber pada kenaikan harga bahan pangan dan energi yang terjadi baik di pasar internasional maupun domestik. Namun, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil di tingkat pusat dan daerah guna mengendalikan inflasi. Laju inflasi tahun 2011 diperkirakan sekitar 5,65 persen. Kedepannya, pemerintah memperkirakan angka inflasi berkisar antara 4 – 5,3 persen. Walaupun tekanan inflasi sudah menunjukkan kecenderungan menurun, namun risiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi. Harga pangan dan harga energi yang cenderung naik menimbulkan peningkatan risiko inflasi mengingat harga pangan dan harga energi menyumbang bobot terbesar terhadap perhitungan inflasi. Perkembangan Inflasi Indonesia Sumber : BPS Secara umum, kebijakan Fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi meliputi 1) kebijakan tarif, 2) kebijakan perpajakan, 3) kebijakan subsidi, dan 4) alokasi belanja lainnya. Terkait dengan kenaikan harga pangan pokok yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah 385 di pasar internasional, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi gejolak kenaikan harga pangan pokok tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain: (i) melakukan operasi pasar yang akan dilakukan di seluruh Indonesia terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, termasuk melalui pola komersial; (ii) pemberian insentif fiskal perdagangan atas ekspor dan impor terkait dengan keringanan Bea Masuk dan fasilitas PPN DTP; (iii) meningkatkan stok pangan yang cukup, di tingkat pusat maupun di daerah dan di masyarakat (lumbung pangan) untuk mencegah spekulasi; serta (iv) menjaga kelancaran distribusi angkutan pangan pokok. Sementara itu, realisasi subsidi non-energi sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai Rp74,2 triliun atau 70,6 persen lebih tinggi dari realisasi 2009. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya realisasi subsidi non-energi 2010 adalah pembayaran kekurangan PPN DTP atas BBM bersubsidi tahun 2003-2005 dan tahun 2009 sebesar Rp22,9 triliun, yang ditampung pada belanja subsidi pajak. Selain itu, meningkatnya realisasi subsidi non-energi juga berkaitan dengan adanya pemberian subsidi pangan ke-13 untuk masyarakat miskin. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas pangan dunia yang berimbas di dalam negeri. Untuk menjaga kenaikan harga pangan, pemerintah mengambil beberapa langkah komprehensif antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, penggunaan dana stabilisasi harga, peningkatan stok beras, peningkatan koordinasi dengan Bank Indonesia, serta penurunan tarif bea masuk impor beras untuk sementara waktu. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif akibat gejolak harga pangan yang terjadi pada tahun 2011 ini, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan antara lain: (i) pemberian kewenangan kepada Kementerian Pertanian untuk menyalurkan bantuan biaya usaha tani bagi daerah atau petani yang mengalami puso dan terkena bencana akibat iklim ekstrim (Inpres Nomor 5 Tahun 2011); (ii) pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) 386 kepada petani melalui kelompok tani, yang meliputi benih Padi, Jagung, dan Kedelai (Perpres Nomor 14 Tahun 2011); (iii) Pengalokasian anggaran untuk Cadangan Benih Nasional (CBN), Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta Cadangan Stabilisasi Harga Pangan; dan (iv) fleksibilitas pembelian harga gabah petani (Inpres Nomor 8 tahun 2011). Kebijakan Penurunanan BM dan PPN DTP secara umum berdampak pada penurunan beberapa komoditas pangan strategis. Kebijakan penurunan BM beras yang dilaksanakan sebelum masuknya musim panen turut mempengaruhi penurunan harga beras secara signifikan, meskipun pada periode yang sama harga di pasar internasional naik. Selain harga CPO internasional menurun, kebijakan PPN DTP minyak goreng turut menyumbang pada penurunan harga minyak goreng di dalam negeri. Pemerintah juga berupaya menciptakan kestabilan harga tepung di dalam negeri melalui BM, meskipun harga gandum di pasar dunia berfluktuatif. VI. Penutup Dinamika dan perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan fiskal yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran negara sebagaimana tertuang dalam APBN. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBN. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah senantiasa berupaya merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan 387 pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentunya, agar kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarkat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak. Terakhir, penerapan kebijakan fiskal yang baik dan sehat pada gilirannya juga akan menciptakan sustainabilitas fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang menuju pada kemandirian ekonomi. Pada titik ini, Bangsa Indonesia sudah mempunyai competitive advantages yang berbasis pada sektor primer domestik seperti seperti sektor pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, serta tidak lagi mengandalkan utang sebagai pembiayaan pembangunan. 388 Daftar Pustaka Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, “Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi” Editor: Anggito Abimanyu dan Andie Megantara. Kompas, 2009 Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi Agustus 2008. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi Desember 1998. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi Nopember 1998. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi Oktober 1998. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi Oktober 2008. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi September 1998. Bank Indonesia. ”Statistik Perbankan.” Edisi September 2008. Bird, Graham and Rowland Dane. “Do IMF Program Have a Catalytic Effect on Other International Capital Flows?”. Oxford Development Studies, 2002 Boorman J and Hume R Andrea. “Life with the IMF: Indonesia’s Choices For The Future”. Kongres ISEI ke-XV, Malang, Juli 2003 Consensus Economics Inc. “Consensus Forecasts. “ London, United Kingdom, Nopember 2008. International Monetary Funds (IMF). Kementerian Keuangan RI, “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012” McLeod, Ross H. “Dealing with Bank System Failure: Indonesia, 19972002”. Indonesia Projet, Economics Division, The Australian National University, 2002 Muhamad Hisyam, 2003, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Yayasan Obor Indonesia Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun 1969/1970 Nota Keuangan pada Rencana Uncang-Undang APBN Triwulan I Tahun 1969 (Januari s.d Maret 1969) 389 Organisation for Economic and Cooperation Development. “Economic Outlook No. 84” Paris, November 2008. Republik Indonesia. “Nota Keuangan dan RAPBN 1998/1999.” Republik Indonesia. “Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000.” Republik Indonesia. “Nota Keuangan dan RAPBN 2000.” Republik Indonesia. “Nota Keuangan dan RAPBN 2008.” Republik Indonesia. “Nota Keuangan dan RAPBN 2009.” Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK. 01/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur.” Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Amandemen UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.” Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.” Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.” Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.” Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.” 390 WHAT ASEAN+3 COUNTRIES CAN DO TO REBALANCE THE GLOBAL ECONOMY1 Anwar Nasution2 1. Introduction The current path of global imbalances seems to be unsustainable and bad for the interests of ASEAN+3 countries3. To continue to prosper, the export-oriented ASEAN+3 needs a healthy international economic system with an open trading system and free capital flows. Solving these problems requires corrections of internal and external balances by both the surplus and deficit countries. Sharp exchange rate adjustments, particularly a large fall in the US dollar caused by a protectionist backlash against the current account deficit, are in no one’s interest as they could disrupt the global economy. Imposition of the emergency countervailing tariffs by the United States to correct the implicit subsidy on Chinese exports through undervaluation of the Renminbi (RBM) will a ignite global trade war and break the world trading system apart. The ASEAN+3 economies with huge foreign exchange reserves can make seven contributions to address the global current account imbalances. 1 2 3 A note presented at Seoul Roundtable on Strong, Sustainable and Balanced Growth in Asia-Pacific, co-organized by Korea National Committee on Pacific Economic Cooperation (KOPEC), Indonesian National Committee on Pacific Economic Cooperation (INCPEC) and East Asian Bureau of Economic Research (EABER) at ANU, Australia, Hotel Shilla, Marronnier Room, 3rd fl., Monday, October 4, 2010. Professor Anwar Nasution teaches economics at University of Indonesia in Jakarta, Indonesia. His e-mail addresses are: [email protected] and [email protected]. The ASEAN+3 countries comprise the 10 members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) plus the People’s Republic of China, Japan and the Republic of Korea. ASEAN is made up of Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. 391 First, to promote a growth strategy that is geared towards domestic demand and reduction of trade surplus through a loose fiscal policy, tight monetary policy, real exchange appreciation and removal of the remaining restrictions on imports. The ASEAN+3 should replace the undervalued exchange rate with increasing productivity a policy instrument in their export-led growth strategy. The labor surplus economies, such as the PRC and Indonesia can exploit their labor surpluses to enhance international competitiveness. The tight monetary policy will control inflation rates and continue to attract capital inflows and pushing up the exchange rate. Second, to modernize and strengthen their underdeveloped domestic financial systems that are still mainly centered around banking system with the long tradition of financial repression. Third, to reduce household savings by building a modern social safety net, including pension funds. Fourth, being the largest economy in Asia, the PRC is expected to gradually shift to fully convertible currency and relax controls on inward and outward movements of capital. This is one of the key prerequisites for making the RMB an international currency. The pace of the shift to convertible currency and liberalization of the capital account depends on the progress of the rebuilding of its domestic financial system. These policy mixes should also be accompanied by further deregulation in the real sector of the economy, including the labor market. These domestic reforms and reforms on international and regional financial systems are crucial for rebalancing global economic growth. The fifth contribution this region can make is to pursue a higher degree of regional trade and investment integration in line with open regionalism that promotes higher efficiency, productivity and economic growth. Aside from the FTAs, that have been rapidly proliferated in this region, there is also a need for investment to build infrastructure in the poorly connected part of the region, particularly in GMS--Greater Mekong Sub-region (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam). In line with the New Miyazawa Plan, the infrastructure projects can be financed by longterm bonds. This region has rich natural resources and fertile agriculture land but is less integrated with the regional production system because of 392 poor infrastructure. The larger intra regional trade will partly offset the falling exports to the US and Europe, the principal export destinations of this region. Sixth, to allow the US to adopt a gradual reform policy. Diversifying portfolios away from dollar-denominated assets would put upward pressure on US interest rates and lead to a fall in the value of dollar to force the US to adopt protectionist policies. All of these would cause a potentially deeper and loner recession in the US economy that could rapidly spread to other parts of the world. Those countries facing high debt-to-GDP ratio and long-term fiscal imbalances in Greater Mekong sub-region, the Philippines and Indonesia have limited fiscal space and, therefore, require a different policy mix. The policy includes both tight fiscal policy and monetary policy and a depreciation of exchange rate. Because of the limitations of the public sector, the private sector should be encouraged to invest in long-term infrastructure projects in these less affluent countries. 2. Deep integration and vertical trade in ASEAN+3 region Chinese economy is now closely linked to its regional neighbors, and particularly with the ASEAN+3 countries. Nevertheless, the patterns of integration between the PRC and her neighboring countries vary substantially. China imports sophisticated capital goods and more advanced parts and components from Japan, Korea and Taiwan to be assembled in the export-oriented plants and export the final products to international markets, particularly the US and the European Union. The more advanced ASEAN-5 countries (Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines) export less sophisticated parts and components mainly for making semiconductors and personal computers. Growing regional trade in parts and computers indicates stronger economic complementary or deeper economic integration and stronger vertical trade in this region. The imported products that are to be re-exported are exempted from import duties and over a half of China’s exports are produced by foreign owned or in joint venture with foreign partners. Because of these, a large part of 393 earnings of the export-oriented plants are accrued to foreigners (Cooper, 2005). The less developed ASEAN countries of the Mekong sub-region selling unsustainable raw materials, food and resources-based products to the fast growing market of China. The broad-based industrial development in the PRC requires many different types of raw materials. Energy consumption is growing fast due to rapid industrialization, urbanization and motorization. Demand for food is rising fast due to rising consumer incomes, urbanization, and demographic changes including female participation rates. Following its predecessors in East Asia and ASEAN regions, the PRC has adopted currency undervaluation as one of the key policy instruments of export-led development strategy. Exchange rate undervaluation is the most powerful policy instrument to promote export and raise productivity in emerging economies, including in the PRC. On domestic front, such a policy has been used to shift allocations of economic resources from nontraded sector of the economy with low productivity to more productive traded sector. Dani Rodrik (2010) estimates that resource reallocation because of the undervalued RMB has raised the PRC long-term growth rate by more than 2 percent. The authorities in the PRC have skillfully used the undervaluation of exchange rate policy in combination with other distorted policies and exploitation of natural endowments of the country to enhance its international competitiveness and raise productivity. The distorted policies include repressed financial system with directed lending, subsidized interest rated and low risks (Calomiris, 207), energy and electricity prices (Liu, 2010), disregards of the environment (Yiping and Tao, 2010). The PRC’s natural resources includes her abundant labor supply (Yao, 2010). On top of these, the authorities in the PRC also raise productive public investment in human capital and infrastructure contributing to productive capacity and improving the economy’s potential output in the long-run. Undervaluation of RMB commands the world’s attention because the PRC is a much bigger country in size than that of Japan, Korea, Taiwan and other export-oriented East and South East Asian countries. The 394 economic growth in the PRC (at 9-10 percent per annum during the past three decades) has also been much higher than of in other Asian countries. Except the capital control, the PRC’s economy is an open economy. As a result, the combination of size, fast growth and openness make China’s effect more significant on the world economy (Humphrey and Schmitz, 2007). Starting from the first semester of 2010, the PRC’s GDP is now surpassing that of Japan to become the number two economy in the world after the United States. At more than $2,5 trillions, the PRC’s external reserves is now the biggest in the world. The level of this reserve is much larger than that required on prudential justification such as import financing and servicing foreign obligations of the country. Like in other countries, the People’s Bank of China (PBC), the central bank, manages the liquid component of the reserves for foreign exchange management. The investment part of foreign exchange reserves is managed by an independent China Investment Company, Ltd, a state-owned Sovereign Wealth Fund, and placed in high-yield and less liquid portfolio investment overseas. Under the capital control, government has the monopoly right to invest abroad representing all economic agents. Correcting undervaluation of the Renminbi (RBM) is one of essential policies for rebalancing economic growth of the world and this region. The issue is not only relevant to the US and the PRC bilateral relations (Bergsten, 2010) but also to other countries as well. The manufacturing sector in many emerging economies, including ASEAN, cannot compete with low cost agriculture and manufactured products made in China. They are the main victims of such a distorted exchange rate policy of the PRC. Attracted by large the gap between economic growth and interest rate short-term capital is massively flowing from advanced economies and in emerging markets. To stem the capital inflows, many emerging economies adopt a combination of currency appreciation, reserve accumulation and various forms of capital controls. Exchange rate appreciation is detrimental to their exports and economic growth. Thailand reinstated a 15 percent 395 withholding tax on interest payments and capital gains on bonds held by foreigners. Korea limits short-term foreign currency borrowings by commercial banks. Indonesia lengthen holding period of short-term capital inflows. Even Japan and Switzerland weaken their currencies to boost exports and economic growth. 3. Exchange Rate Management At present, the ASEAN+3 economies adopt a variety of exchange rate management systems (Table 1). According to the Impossible Trinity or the macroeconomic trilemma, policy makers in an open economy have to make two choices out of the following three goals, namely: (i) monetary independence, (ii) fixed exchange rate and (iii) free movement of international capital. Only country with strict capital control, such as the PRC can have monetary independence and fixed exchange rates. Along with the control of short-term capital movements, Malaysia moved in 1997 from managed floating to strict pegging. Other ASEAN+3 economies with free capital mobility could only choose between exchange rate targeting and monetary (money supply or interest rate) targeting. 396 Table 1. Elements of Monetary Policy in ASEAN + 3 Countries following the Asia Financial Crisis of 1997 Under the IMF programs, exchange rate policies in Thailand, Indonesia and Korea shifted to independent floating in 1997, supported by inflation targeting as a monetary policy operating strategy. This means that an exchange rate target is no longer used as a nominal anchor for monetary policy. Cambodia and Singapore maintain the managed floating system and leaving money supply and interest rate to be determined by the market. Myanmar, Vietnam and China preserve strict pegging while Brunei and Hong Kong continue to adopt the currency board system under which money supply is backed up by the US dollar at the official exchange rate. 397 The maintenance of inflation targeting as an operating strategy of monetary policy in Indonesia, Korea, Philippines and Thailand long after the end of the IMF programs indicates their firm commitments to price stability, disclosure, transparency, central bank independence and refraining from printing money to finance budget deficits. An explicit inflation target, along with a more flexible exchange rate regime and a mechanism that ensures a stable government debt-to-GDP ratio are now the three main pillars of macroeconomic stabilization frameworks in these countries. Central bank accountability under the inflation targeting framework imposes costs on incompetent and opportunistic central banks. China and Malaysia announced on July 21, 2005 a policy switch to an adjustable peg against undisclosed baskets of currencies. Prior to this, Malaysia had ended partial capital controls introduced during the Asian financial crisis in 1997. The revaluation of the RMB is a small step to the right direction, but maintaining a very narrow 0.3 percent daily limit on renminbi-dollar fluctuations is too restrictive. 4. Accumulation of Foreign Exchange Reserves In reality, not all countries in ASEAN+3 practise strict inflation targeting, with some having adopted more flexible policies. Aside from inflation, the policy objectives of the central banks of many countries also include exchange rate stability but they are not any more setting of exchangerate targets (Filardo and Genberg, 2009). As pointed out by Calvo and Reinhart (2002), because of the ‘fear of floating’, avoiding large exchange rate fluctuations continues to play a significant role in the monetary policy of emerging economies so as to avoid adverse impacts on their economies. There are four factors that drive this fear of floating, namely: (i) the fear of increases in foreign liabilities denominated in foreign currencies, (ii) the fear of output costs associated with exchange rate fluctuations, (iii) the fear of inelastic supply of funds during times of crisis; and (iv) the fear of losing credibility and accesses on the international capital markets. 398 Flexible exchange rate requires a smaller war chest of external reserves as the system reduces the need for market intervention. In reality, for a number of reasons, Asian countries accumulating large international reserves following the Asian financial crisis in 1997-98 (Ruiz-Arranz and Zavadjil, 2008). The first reason, as discussed earlier, is to stabilize exchange rate and avoid excessive exchange rate appreciation. An appreciated exchange rate makes import cheaper and reduces competitiveness of exports. At the same time, such an overvalued exchange rate discourages reallocation of resources from the less productive non-traded sector of the economy to the more productive traded sector. Second, is to prepare for a defense against speculative attack and foreign exchange rate instability due to shortfalls in exports and to capital flow reversals. Third, the less volatile exchange rate eliminates currency risks and provides incentives for overseas borrowing, particularly when international interest rates are lower than domestic interest rates. The fourth reason is for the external reserve accumulation is to provide for a fiscal space when facing the crisis. The bitter experience of Asian financial crisis in 1997 was associated with the IMF conditionality to adopt pro-cyclical macroeconomic policy, including tight fiscal policy, high interest rate and large exchange rate devaluation during the crisis that had over killed their banks, corporations and the economy and caused wide political and social implications. Because they were treated badly when they sought help in the past, Asian countries are quite reluctant to turn to the IMF. At that time the crisis hit countries recovered quickly by devaluating their national currencies to boost exports. During the recent global financial crisis in 2007-08, as the world economy was in recession, exchange rate devaluation could not be effective to stimulate the economy. Monetary policy was powerless as interest rate was already close to zero. Under liquidity trap, fiscal policy is the only hope to get out of recession. But, only those with adequate external reserves, access to external financing can afford the cost of fiscal stimulus. At the same time, reserves availability would increase the scope for accommodating monetary policy, relaxing domestic financial constraints and reducing the risk of crowding out 399 private activity. In addition, reserve adequacy would improve credit rating, reducing the risk premium on external financing. ASEAN+3 countries have introduced a number of policy measures to protect their financial systems from the recent global turmoil of 2007-08. In line with the policies adopted elsewhere, the authorities of this region temporarily banned short selling of equity shares of financial institutions. Non-viable and non-systemic banks have been allowed to go bankrupt. The supply of liquidity in domestic currencies has been augmented by reducing the minimum reserve ratio requirements and introducing emergency credit facilities. Japan continues to apply monetary easing by supplying liquidity to the market and reducing nominal interest rates close to zero. The quantitative easing monetary policy in Japan has been in place since the instability in its financial system in the 1990s. 5. Mixed economic system and leading role of banking industry The economies of many ASEAN+3 countries are mixed economies rather than fully fledged market-based ones. Government plays an important role in these economies, either as a regulator or as a direct producer of private goods through vast networks of state-owned enterprises (SOEs) covering many sectors of the economy, including banking. The roles of the SOEs are still dominant not only in the socialist countries such as the PRC, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar, but also in Indonesia and Singapore. The day-to-day operations of many SOEs in many Asian countries, except in Singapore, are tightly controlled by the state and they operate like arm’s length extensions of the government bureaucracy. For a long period in the past, nearly all of the ASEAN+3 countries applied industrial policies. In terms of assets and branch networks, the banking industry is the core of the financial systems in the ASEAN+3 (Table 2). Except in Hong Kong and Japan, the role of non-bank financial institutions (NBFIs) is relatively small as insurance companies and pension funds are still underdeveloped. Because of the availability of cheap and low risk program loans from the 400 Public Sector Banks (PBS) under the long period of financial repression in the past, there was no incentive for economic agents to raise funds from stock and bond markets. Market capitalizations are particularly high in Singapore and Hong Kong, the main financial centers of the region. During the Cold War, it was relatively easy for governments to finance their budget deficits from highly politicized foreign aid. Because of this there was no need to issue sovereign bonds for financing budget deficit. PBS plays a prominent role in the banking system of most of the ASEAN+3 countries. The role of state-owned banks is dominant in China, Indonesia and GMS. Both central and provincial governments have their own deposit-taking banks and many lower layers of government own rural credit institutions that compete with money lenders. Under the financial repressions of the past, there was no incentive for bank managers to monitor and manage risks, to upgrade transparency in corporate reporting or to provide economically relevant information. All private-owned banks in this region belong to business conglomerates. Because of the distorted market information due to weak legal and accounting systems, these banks mainly provide loans to those they know best, namely, their affiliated companies. To take benefit of lower international interest rate, with perceived zero foreign exchange risk under the fixed exchange rate system, both banks and reputable companies before the crisis in 1997 heavily borrowed shortterm loans in foreign currencies from international markets to finance long-term projects at home including in non-traded sector of the economy. Such practices have caused double maturity and currency mismatches that ignited financial crisis in 1997. 401 Table 2. Size and Composition of Financial System (% of GDP) Financial Sector Assets1 Country Deposit-taking Financial Institutions 2000 2008 Non-bank Financial Institutions 2000 2008 Market Capitalization2 2000 Total Bonds Outstanding 2008 2000 2008 China 168.8 204.5 8.8 33.9 27.1 32.3 16.9 50.3 Hong Kong 505.5 640.7 196.4 573.8 363.9 610.9 35.8 42.9 India3 61.6 91.6 15.4 32.8 33.3 59.7 24.6 35.3 Indonesia 63.6 48.6 8.8 13.7 18.7 21.7 31.9 13.4 Korea 147.9 192.7 44.1 62.6 31.2 56.3 66.5 86.2 Malaysia 154.2 190.3 16.5 20.2 124.7 89.6 74.8 73.5 Philippines 99.2 78.8 22.4 18.5 76.8 54.3 27.6 33.7 Singapore 683.8 707.9 39.1 47.1 243.7 148.0 48.0 70.8 Taipei, China 259.9 289.6 29.8 80.6 81.7 94.7 7.7 7.7 Thailand 132.3 137.7 10.7 33.0 26.0 39.2 25.3 51.6 Average4 227.7 258.2 39.2 91.6 102.7 120.7 35.9 46.5 Median 151.1 191.5 19.5 33.4 55.1 58.0 29.8 46.6 Eurozone 230.0 315.8 142.1 169.3 - - 124.2 69.4 Japan 227.5 230.9 118.5 132.1 71.7 55.8 97.4 193.4 78.3 104.8 283.2 306.1 117.5 64.6 41.8 55.3 United States Source: Chee Sung Lee and Cyn-Young Park. 2009. Beyond the Crisis: Financial Regulatory Reform in Emerging Asia. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No.34. September, Table1 Page 12. Notes: 1. Financial asset data for People’s Rep of China (PRC) for 2002 and 2007; Hong Kong, China, for 2000 and 2007; Indonesia for 2001 and 2007; Malaysia for 2000 and 2007; and Japan for 2001 and 2004. 2. Market capitalization as percentage of gross domestic product (GDP) in local currency. 3. Financial sector assets data for India in 2000 refers to FY ending March 2000; and for 2008 ending March 2008. 4. Simple average 402 The Asian crisis of 1997 marks the beginning of major reform in Asian financial system to move from financial repressions to market-based system in line with the Basel core principles. Healthier market competition was encouraged by allowing greater penetration of foreign banks and financial institutions in domestic market through privatization, merger and acquisition. Market infrastructure has been much improved through overhauling of prudential regulations, supervision standards and practices. Safety nets were established, including deposit insurance companies and the Financial Stability Forums. The unlimited blanket guarantee schemes have been replaced by the deposit insurance companies to protect limited amounts owned by small depositors. Accounting and reporting systems and credit bureaus have been improved and established to upgrade information system. 6. Bond markets Both the governments and the central banks in six ASEAN+3 countries issue competing interest bearing bonds and securities. The six countries are Indonesia, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and the PRC (the People’s Republic of China) Interest bearing bonds and securities are used by the central banks as instruments for open market operations and to sterilize accumulations of foreign exchange reserves. Bank Indonesia has issued interest-bearing certificates of deposit (SBI-Sertifikat Bank Indonesia) since 1974 in the absence of both short-term Treasury bills and government bonds. Some countries, such as the PRC and Korea, recently issued interest bearing bills as they ran out of government papers to sell to sterilize purchases of foreign exchange. Particularly during the Cold War, budget deficits in the public sector in some ASEAN+3 member countries were also financed by official development aid at concessionary terms. Because of the availability of cheap and low-risk credit from the banks during the past policies of financial repression, there was no incentive for the corporate sector to raise funds from the capital and securities markets. On top of this, tax policies, such as stamp duty on transfers of bond 403 ownership, impeded the development of the secondary bond markets. On the demand side, institutional investors, such as insurance companies and pension funds, were not yet developed. As a result, both the private sector and public sector were heavily reliant on short-term borrowing from the banking system. Bond market and securitization started to grow in ASEAN+3 after the credit crunch following the bankruptcy of major banks in 1997. After the financial crisis in 1997, the ASEAN+3 and EMEAP4 countries adopted a combination of a market-led and government-led strategies to develop domestic and regional bond markets. To create and improve the working of domestic bond markets and promote their regional integration, both the central banks of EMEAP and the Ministers of Finance of ASEAN+3 have taken measures to improve and harmonize market infrastructures. The governments have also helped to establish rating agencies, introduce credit guarantee schemes, and enhance securitization. The menus offered by regional bond markets have been diversified through the issuance of large amounts and greater diversity of government bonds. Table 3 shows the rapid growth of Asian bond markets between 1997 and 2004. Government bonds play a dominant role in the structure of the bond markets in China, Indonesia, Korea, Singapore and Thailand. The rapid growth in the issuance of government bonds following the financial crisis in 1997 in Indonesia, Thailand and Korea was mainly for the purpose of financing bank recapitalization and the restructuring of bank clients in the corporate sector. In 1998-1999, Indonesia issued government bonds for its bank recapitalization program amounting to Rp 640 trillion, or was roughly equivalent to 50 percent of her annual GDP in 1999. The rapid growth of the bond market in Malaysia has been mainly due to the government’s initiative to promote the issuance of corporate sector bonds. The sovereign bond markets in Singapore and Hong Kong are relatively 4 EMEAP, or the Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks, has 11 members, namely, the Reserve Bank of Australia, People’s Bank of China, Hong Kong Monetary Authority, Bank Indonesia, Bank of Japan, the Bank of Korea, Bank Negara Malaysia, Reserve Bank of New Zealand, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore and Bank of Thailand. 404 small due to the balanced budget policy applied by these countries. By contrast, Indonesia changed her debt strategy after the Asian financial crisis in 1997 to one of financing its budget deficit with government bonds issued both on the domestic and overseas markets. The drying up in bank lending has encouraged non-bank and nonfinancial institutions in this region to provide funds by securitization built around asset-backed securities supported by lease and credit receivables. Governments, such as that of Japan, have also been active in promoting the securitization markets. To replace the Fiscal Investment and Loan Program (FILP) as a provider of credit to small and medium enterprises (SMEs), the Government of Japan has established the JASME (Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprises), a specialized financial institution to provide government program loans to this class of customers. JASME receives a guaranteed lending facility through the credit guarantee corporation, and other credit enhancements (Sekine, et.al., 2009). Table 3. Size of Asian Bond Markets 1997 2004 Country Outstanding ($ million) Percentage Outstanding of GDP ($ million) Percentage of GDP China 116.4 12.9 483.3 24.9 Indonesia 4.5 1.9 57.7 22.7 Korea 130.3 25.1 568.3 83.2 Malaysia 57.0 57.0 106.6 90.0 Philippines 18.5 22.3 25.0 28.8 Thailand 10.7 7.1 66.5 41.1 Hong Kong 45.8 25.9 76.8 46.3 Singapore 24.7 78.6 73.1 23.7 405 Japan 4,433.6 97.6 8,866.7 197.7 USA 12,656.9 62.9 19,186.6 161.6 Source: Eiichi Sekine, Kei Kodachi, Tetsuya Kamiyama, The Development and Future of Securitization in Asia, Table 7.1 in Yasuyuki Fuchita (et. al) 2009, Chapter 7. 7. International and Regional Financial Architectures In addition to currency undervaluation, reforming international and regional monetary systems are also crucial for rebalancing economic growth. Regaining trust and confidence in the IMF as an international institution to provide financial assistance to its member countries in need will reduce the need for building individual reserves. The recent crises in East and Central Europe and Greece indicate that the world needs regional financial institutions to augment the IMF financing, surveillance and conditionality. The London Summit of G-20 in April 2009 gave a renewed mandate and greater financial resources to the IMF and agreed to reform international financial architecture. These allowed the IMF to rebuild trust by overhauling its lending framework by modifying its policy recommendation and conditionality and making them more flexible and can be tailored to the needs of individual borrowers. The IMF now supports countercyclical policies and even temporary imposition of capital controls to deter currency speculators. During his visit to Seoul in July 2010, Mr. Strauss-Kahn, publicly acknowledged the IMF’s policy mistakes in handling the Asian financial crisis in 1997. The reform will raise the IMF quota and voting power of Asia in the Fund and reduce the representation of the European on the Executive Board. The increasing Asia’s voice and representation in the Bretton Woods financial organizations as well as the changes in its policy prescriptions are expected to have greater placement of large reserves of Asia countries 406 in them. Only with sufficient financial resources can the IMF provide stronger financial safety net closer to being an international lender of last resort as proposed by the Korean authorities. In addition to greater financial resources, the IMF also needs to strengthen its supervision and conditionality to limit the borrowers from taking excessive risks to their portfolio that caused moral hazard problems. As shown by experiences of ASEAN+3 countries during the recent crisis in 2008, the availability of the currency swap facilities from Chiang Mai Initiative (CMI) and neighboring countries have substantially added to foreign reserves to cover short-term foreign currency debt, provide a fiscal space and increase the scope for accommodating monetary policy. At that time, South Korea received currency swap facility from Japan and the PRC as well as the US Federal Reserve Bank. The establishment of a European Financial Stabilization Facility (EFSF) in Eurozone in May this year following the crises in East, Central and Southern Europe also indicates the need for regional financial arrangements to supplement the IMF resources and surveillance. The need for individual reserves in this region will be further reduced by the strategic decisions on the CMI made by the finance ministers of the ASEAN+3 countries during their meetings in Madrid in 2008. They agreed to multilateralize BSA (Bilateral Swap Arrangements), to enlarge the size of the currency swap facility and to increase the portion that is non-linked to an IMF program. Chiang Mai Initiative Multi-lateralization (CMIM) is a great leap forward toward greater political cohesion in the ASEAN+3 countries as they transfer some national powers to a regional institution. Established in March 2010, the CMIM is a common swap arrangement of $120 billion. To do surveillance the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) will be established in May 2011 replacing the ASEAN+3 Economic Policy Review and Policy Dialogue. CMIM will result in the pooled fund becoming self-managed under a single contract, thus reducing costly bilateral transactions and wasteful duplication of loan contracts. The PRC is now very keen to support establishment of the quota-based 407 CMIM to pool resources through tapping of the region’s huge external reserves for supplementing IMF facilities. During the Annual Meetings of the IMF and the World Bank in Hong Kong, in 1997, the PRC along with the US and EU strongly opposed Japanese proposal to establish the Asian Monetary Fund. The PRC at present sees the MCMI as a platform for internationalization of RMB. Aside from establishing currency swap lines with its trading partners, the RMB are now being used as invoicing and trade settlements with its regional neighbors. Malaysia’s central bank has recently bought renminbi-denominated bonds for its external reserves (Financial Times, September 20, 2010). Moving forward, the ASEAN+3 countries also need to strengthen regional cooperation to build up their financial systems and contribute to Basel III negotiations. The first area of cooperation would be to continue the existing regional programs to develop the bond and capital markets. The existence of more matured national and regional bond markets allows ASEAN+3 to tap financial resources of their regional neighbors. The second area would be to reorganize and enlarge the SEANZA5 forum by establishing a college of regional bank supervisors to discuss common interests. All of ASEAN+3 countries are in transition from state-led financial repressions to market based system. The agenda would cover comparing notes and harmonizing bank resolution and insolvency procedures, the transition to a market-based system, corporate governance, how to corporatize and privatize public sector banks, how to deal with related lending of private banks, and the application of the risk-based Basel III regulatory and supervisory framework to all banks regardless of ownership. Narrow banks can be established with a special mission to administer government directed lending programs. T The third area of cooperation would be to discuss and adopt a common stance on the harmonization of capital rules and supervisory practices in the region, and to anticipate the implications of the recent discussions 5 Established in 1956, SEANZA (South East Asia, New Zealand and Australia Central Banks) has two subsidiaries, namely, SEACEN and SEANZA Forum for Bank Supervisors. SEACEN is a training center and research organization based in Kuala Lumpur. 408 in international forums, such as the BIS and G-20, on the expansion of regulatory and supervisory perimeters to non-bank affiliates, increasing minimum capital for total and Tier 1 element risks under the Basel framework, and the introduction of minimum leverage ratios for bank capital, on their banks, corporations and developmental strategies. The invitation of some emerging economies to join BIS and the establishment of the Hong Kong Representative Office of BIS in 2002 were partly intended to incorporate regional inputs in “the Asian way” in the universal banking regulations and supervisory standards. Traditionally, the BIS standards were exclusively tailored to the needs of the well developed banking systems and matured financial markets in Europe and the United States. The college of regional bank supervisors would not only supervise the operations of regional financial firms, but it would also discuss the implications of the proposals of the expansion of capital requirements and accounting standards on quasi fiscal operations, public sector companies (including banks), and affiliated companies (both shadow banks and non-financial corporations), and off-balance sheet items. The setters of accounting standards in the region should work on how to improve credit and collateral valuation standards in regards to business affiliates to avoid principal-agent and insider-trading problems. Other topics of common interest would include how to avoid pro-cyclicality and minimize deposit insurance rates. Based on their historical experiences and Asian culture, the nations of this region need to contribute to the global discussions on these issues. Supervisory coordination, however, should not extend to the creation of a safety net as ASEAN+3 is not a monetary union. October 1, 2010. 409 References Bergsten, C. Fred. 2010. Correcting the Chinese Exchange Rate. Testimony before the Hearing on China’s Exchange Rate Policy, Committee on Ways and Means, US House of Representatives, Washington, D.C. September 11. “Bond boost for renminbi”, Financial Times, Asia, Monday, September 20, 2010, p.1. Calomiris, Charles A. ed. 2007. China’s Financial Transition at a Crossroad. New York: Columbia University Press. Calvo, Guilermo A. and Carmen M. Reinhart. 200. “Fear of Floating”. Quarterly Journal of Economics. 117:379-408. Cooper, R.N. 2005. Living with Global Imbalances: A Contrarian View. Prolicy Brief in International Economics. No. PB05-3. November. Eichengreen, B. 2004. “Hanging Together? On Monetary and Financial Cooperation”. In Shahid Yusuf, M.A. Altaf and Kaoru Nabeshima. Eds. 2004. Global Change and East Asian Policy Initiatives. Washington, D.C.: The World Bank. Filardo, Andrew and Hans Genberg. 2009. Targeting Inflation in Asia and the Pacific: lessons from the recent past. Hong Kong: BIS Representative Office for Asia and the Pacific. August. Humphrey, John and Hubert Schmitz. 2007. China: Its Impacts on Developing Asia Economies. Working Paper 295. Institute of Development Studies at the University of Sussex. December. Liu, Guy and Liang Zhang. 2010. Rethink of Price Regulation: a case of electricity pricing In China. A paper presented at Asian Economic Panel Meeting at Keio University, September 11-12. 410 Nasution, Anwar. 2007. What East Asian countries should do to address global saving-investment imbalances”. East Asia Economic Papers. 6(2):1-13. Spring/Summer. _____________ 2010. Building Strong Banks and Bond Markets in the ASEAN+3 Countries, A paper presented at the International Conference on “A perspective of Asian Financial Sector under the Global Financial Crisis”, jointly organized by the Japanese FSA-IMF-ADBI, Tokyo, January 21. Nishihara, Rie. 2005. Central Banks and Bond Market Development in EMEAP Countries. Tokyo: Bank of Japan. June 18. Pak, Yung Chul. 2010. “RMB Internationalization: Its Implication for Financial and Monetary Co-operation in East Asia”, a paper presented at Asian Economic Panel Meeting, Sheraton Incheon Hotel, Incheron, Korea, March 22-23, 2010. Rodrik, Dani. 2010. “Making Room for China in the World Economy”. Papers and Proceedings of the 122 Annual Meeting of the AEA, Atlanta, Ga, January 4-6, 2010. AER: 89-93. Ruiz-Arranz, Marta and Milan Zavadjil. 2008. Are Emerging Asia’s Reserves Really Too High?. IMF Working Paper. No. WP/08/192. August. Stiglitz, Joseph E. and Members of a UN Commission of Financial Experts. 2010. The Stiglitz Report. New York: the New Press. Truman, Edwin M. 2010. “The G-20 and International Financial Institution Governance”. Working Paper Series. No. WP 10-13. Peterson Institute for International Economics. September Yao, Yang. 2010. China’s Export-led Growth Model: Causes, Prospects and Structural Issues. A paper presented at Asian Economic Panel Meeting at Keio University. September, 11-12. 411 Yiping, Huang and Tao Kunyu. 2010. Causes and Remedies of China’s External Imbalances. A paper presented at Asian Economic Panel Meeting, Sheraton Incheon Hotel, Incheon, Korea. March 22-23. 412 KOORDINASI FISKAL MONETER DALAM JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Anggito Abimanyu, Ph.D. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A. A. Pendahuluan Krisis keuangan di Amerika Serikat sejak tahun 2008 dianggap sebagai krisis terburuk sejak the Great Depression tahun 1930-an. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menurun untuk dua tahun ke depan, walaupun telah membaik di tahun 2010 dari puncak krisis tahun 2009. Namun demikian, pertumbuhan dunia tersebut tetap memberikan sinyal membaiknya kegiatan ekonomi dibandingkan saat krisis tahun 2009. Negara berkembang dan ASEAN 5, dengan menerapkan kebijakan yang strategik, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan momentum krisis ini. 413 Gambar 1.Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Sumber: diolah dari IMF (2011) Negara ASEAN 5, khususnya Indonesia, harus mengidentifikasi dampak dari krisis terhadap sektor keuangan yang menjalar dengan cepat. Identifikasi dampak krisis fokus pada variabel dan parameter di sektor keuangan, tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi.Argumen bahwa perekonomian dapat berdiri di antara krisis ekonomi global tidak sepenuhnya terjustifikasi.Pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar adalah konsumsi rumah tangga.Situasi ini tidaklah optimal jika investasi dan produksi tidak bisa menopang konsumsi tersebut.Indonesia, sebagai kompensasinya, harus mengimpor kebutuhan dari luar negeri.Situasi ini meningkatkan paparan Indonesia terhadap berbagai macam ketidakpastian seperti imported inflation serta gejolak nilai tukar rupiah. 414 Gambar 2. Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham, 2000:012010:03 Sumber: diolah dari IFS, 2011 Economic exposure serta ketatnya likuiditas pasar keuangan internasional memberikan tekanan jangka pendek kepada pasar uang dan pasar modal di Indonesia.Tekanan di pasar uang dan pasar modal tidak hanya mempengaruhi faktor fundamental namun juga faktor psikologis.Faktorfaktor tersebut memberikan andil terhadap depresiasi nilai kurs, seperti dijelaskan Gambar 2.Kurs rupiah melemah hingga kisaran Rp10.225Rp11.575/US$ pada kuartal IV 2008 sampai dengan kuartal II 2009. Indeks harga saham, pada saat yang sama, turun sebesar rerata 15,6% selama tahun 2008 dengan penurunan terbesar sebesar 38,9% pada kuartal IV 2008. Cadangan devisa merupakan pilihan pemerintah, khususnya Bank Indonesia, untuk menjaga nilai tukar rupiah dan psikologis pasar secara tidak langsung. Gambar 3 merekam penurunan cadangan devisa sebesar 4% dan 9,9% pada kuartal III dan IV 2008.Intervensi tersebut ternyata relatif tidak dapat mengimbangi capital flight yang cukup deras pada rentang periode tersebut. 415 Gambar 3. Cadangan Devisa, 2000:01-2010:03 Sumber: diolah dari IFS, 2011 Suku bunga acuan dipertahankan stabil pada kisaran 6% untuk mempertahankan arus devisa yang masuk dan keluar dari Indonesia (Gambar 4). Suku bunga ini relatif yang tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Thailand dan Malaysia bahkan menetapkan suku bunga acuan pada kisaran 3-3,5%. Implikasinya adalah suku bunga kredit riil yang relatif tinggi atau real cost of funyang masih tinggi di Indonesia.Keadaan ini tidak preferable bagi sektor riil yang sebetulnya memiliki potensi untuk memanfaatkan kesempatan di kala pemulihan krisis. Fokus kebijakan tidak hanya tertuju pada pergerakan variabel utama tetapi juga asa dari pelaku pasar.Faktor asa pelaku ekonomi pada masa krisis akan sangat berbeda dengan perilaku pada masa normal. Arus informasi sangat cepat dan seringkali mendorong pelaku ekonomi untuk segera mengambil keputusan karena pelaku ekonomi menghadapi ketidakpastian. Konsekuensinya, volatilitas variabel cenderung meningkat dan proyeksi variabel seringkali meleset dan penerapan kebijakan seperti halnya di masa normal relatif tidak kompeten. 416 Krisis perekonomian juga tidak lepas dari keadaan sektor keuangan. Sektor ini lah yang memiliki potensi besar untuk menerima konsekuensi dari keadaan krisis.Konsekuensi tersebut dapat meliputi kesulitan likuiditas dan penurunan kepercayaan nasabah.Lebih dari itu, pengambil kebijakan juga menghadapi suatu kemungkinan kegagalan lembaga di sistem keuangan, seperti bank, yang berdampak sistemik.Oleh karena itu, pembahasan kebijakan terkait resolusi krisis harus mempertimbangkan keadaan sektor keuangan. Gambar 4.Suku Bunga Kredit Riil Negara ASEAN, Januari 2011 Sumber: Diolah dari berbagai sumber Tanggung jawab pengawasan sektor keuangan paling tidak mengerucut pada koordinasi fiskal dan moneter oleh pemerintah.Kementrian keuangan selaku otoritas fiskal dan otoritas yang berhak menciptakan regulasi harus terus menjalin koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Fokus koordinasi tidak hanya untuk masa normal saja namun lebih kepada masa krisis. Mekanisme koordinasi fiskal dan moneter pada saat krisis merupakan elemen krusial karena kedua otoritas inilah yang memiliki knowledge dan policy tools untuk menghadapi krisis. 417 Pembahasan dalam tulisan ini meliputi kompleksitas sistem keuangan di Indonesia (bagian B) dan Pentingnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan (bagian C).Pembahasan pentingnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi aspek legal, aspek koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan Koordinasi Fiskal Moneter. B. Kompleksitas Sistem Keuangan di Indonesia Lembaga keuangan memiliki ukuran yang besar dalam perekonomian dengan proporsi aset terhadap PDB nominal mencapai 47,6% pada tahun 2008. Profil lembaga keuangan di Indonesia didominasi oleh Perbankan dengan proporsi aset hampir 90% dari aset seluruh lembaga keuangan. Nilai kredit, pembiayaan, pinjaman, dan investasi mengalami pertumbuhan sebesar 24,2% pada tahun 2008, angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Kita lihat modal ventura mengalami peningkatan nilai aktivitas yang cukup pesat yaitu 233,3% diikuti oleh pegadaian (83,7%) dan perbankan (62,5%). Kenaikan nilai aktivitas sektor keuangan paling tidak menjelaskan kenaikan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan. Tabel 1. Aset dan Nilai Aktivitas Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Perbankan (A) LK Nonbank (B) Modal ventura Asuransi Aset (triliun rupiah) 2006 2007 2008 Nilai aktivitas utama (triliun rupiah)1 2006 2007 2008 1.693,5 1.986,5 2.310,6 832,9 1.045,7 1.353,6 3,0 16,2 2,8 19,1 2,1 22,7 1,5 152,9 4,7 202,3 5,0 211,2 Perusahaan pembiayaan 93,1 107,7 137,5 93,1 107,7 137,5 Dana pension 77,7 91,2 90,2 75,0 88,0 86,4 Reksa dana Pegadaian 72,1 18,4 73,1 22,8 74,1 33,8 18,4 22,8 33,8 418 Total Aset LK Nonbank (B) Aset total sektor keuangan (A+B) PDB nominal (triliun rupiah) (C) Proporsi Aset Perbankan: PDB (A:C) Proporsi Aset LK Nonbank: PDB (B:C) Rasio Aset Sektor Keuangan:PDB (A+B):C 280,5 316,7 360,4 340,9 425,5 473,9 1.974,0 2.303,2 2.671,0 1.173,8 1.471,2 1.827,5 3.949,3 4.954,0 5.613,4 3.949,3 4.954,0 5.613,4 42,9 40,1 41,2 21,1 21,1 24,1 7,1 6,4 6,4 8,6 8,6 8,4 50,0 46,5 47,6 29,7 29,7 32,6 Sumber: dihitung dari BI (2010b;2009), Bapepam-LK (2009), Pegadaian (2010)1 Nilai aktivitas berdasarkan jumlah kredit (perbankan), jumlah pinjaman (pegadaian), jumlah pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan modal ventura), dan jumlah investasi (asuransi dan dana pensiun). Industri Perbankan mendominasi sektor keuangan dengan rasio aset mencapai 87%. Dominasi ini rasanya tidak akan banyak berubah dalam waktu dekat walaupun industri modal ventura dan pegadaian berkembang cukup pesat. Sektor keuangan Indonesia, ke depannya, tidak dapat mengesampingkan perkembangan lembaga keuangan mikro (LKM). Usaha yang masuk dalam klasifikasi LKM meliputi bank unit mikro, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), BMT, credit union, dan LSM. Ukuran LKM di Indonesia dalam hal aset tidaklah terlalu besar relatif terhadap industri perbankan, asuransi, modal ventura, dan pegadaian. Namun demikian, jumlah LKM di Indonesia mencapai 35 juta sampai dengan tahun 2009 dan jumlah unit usaha maupun nasabah akan terus bertambah (Pradiptyo dkk., 2010). 419 Gambar 5. Pangsa Aset Lembaga Keuangan Terhadap Total Aset Sektor Keuangan, 2008 Sumber: dihitung dari BI (2010b;2009), Bapepam-LK (2009), Pegadaian (2010) Profil sektor keuangan di Indonesia juga dilengkapi oleh program pinjaman mikro yang jumlahnya mencapai 35.135 program di seluruh Indonesia (Ashari, 2006). Program pinjaman mikro meliputi Kredit Usaha Kesejahteraan Masyarakat (Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Pendidikan Kewirusahaan Masyarakat (PKM), dan Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS). Nasabah yang tercatat mencapai 17 juta dengan total pinjaman Rp2,8 triliun (Pradiptyo dkk., 2010). 420 Gambar 6. Kompleksitas Keterkaitan antar Lembaga Keuangan di Indonesia Sumber: modifikasi dari Pradiptyo dkk., 2010. Seluruh elemen di sektor keuangan, mulai dari bank, lembaga keuangan non-bank, LKM, hingga program mikro, memiliki keterkaitan usaha. Keterkaitan ini tidak terbatas pada transaksi keuangan mutual tetapi juga penanaman modal hingga kepemilikan. Kompleksitas transaksi muncul terutama antara dua lembaga yang berada di payung pengawasan yang berbeda. Sistem pengawasan yang telah ada saat ini, baik Bank Indonesia, Bapepam-LK, maupun Kementrian Koperasi dan UKM, belum memiliki kerjasama terkait data sharing dan data interfacing. Permasalahan yang terjadi adalah sistem pengawasan antar industri yang asimetrik (Gambar 7). Bank Indonesia memiliki sistem yang telah mapan dengan pengawasan on- dan off-site di seluruh Indonesia. Sistem 421 mereka mampu mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan pada saat itu juga. Bapepam-LK saat ini cenderung fokus pada pengawasan laku bisnis atau compliance pemain usaha dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan oleh Bapepam-LK belum mencakup aspek sistemik suatu lembaga keuangan dan industri lembaga keuangan. Kementrian Koperasi dan UKM (KUKM) bahkan belum memiliki sistem pengawasan koperasi yang dapat diterapkan. Gambar 7. Sistem Pengawasan Sektor Keuangan yang Asimetrik Sistem pengawasan Bank Indonesia yang ketat saja masih memungkinkan segelintir pelanggaran. Hal ini memunculkan keraguan terhadap sistem pengawasan oleh Bapepam LK apalagi KUKM. Tidak banyaknya pelanggaran yang dilaporkan di industri yang mereka awasi belum tentu karena sistem pengawasan yang baik namun karena sistem deteksi yang relatif lemah. Playing field yang asimetrik karena kedalaman pengawasan yang berbeda memiliki potensi moral hazard yang tinggi. Investor cenderung untuk mengembangkan pasar di sektor yang memiliki pengawasan yang lebih lemah. Kompleksitas sistem keuangan di Indonesia memerlukan sistem pengawasan yang komprehensif. Lebih dari itu, sistem keuangan di 422 Indonesia memerlukan jaring pengaman untuk menghindari berbagai adverse effect yang muncul di saat krisis. Jaring pengaman sistem keuangan memberikan mandat kepada suatu pihak untuk mengambil keputusan di kala krisis. Mengambil keputusan untuk menyelamatkan sektor keuangan lebih krusial dibanding menghiraukannya sama sekali. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme yang memberikan kewenangan kepada suatu pihak untuk mengambil keputusan di saat krisis. C. Pentingnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan Krisis sektor keuangan di Indonesia pada tahun 1997-1998 terekam sejarah menjadi krisis termahal di dunia. Pengambil kebijakan harus mengeluarkan biaya hingga 50% dari PDB Indonesia pada periode itu untuk menyelamatkan sektor keuangan. Kasus kegagalan lembaga keuangan kembali muncul di krisis keuangan global lalu, seperti Northern Rock di Britania Raya, Hypo Real dan IKB di Jerman, Fortis di Belgia, serta Lehman Brothers di Amerika Serikat terjadi karena absennya special resolution regimeatau crisis resolution regime (Nier, 2009). Special resolution regimeadalah elemen penting kerangka pengambilan kebijakan khusus di masa krisis. Mekanisme resolusi yang disusun sedimikian rupa merupakan langkah untuk mencegah dampak buruk kegagalan lembaga keuangan yang berdampak sistemik. Indonesia, sayangnya, belum memiliki platform resolusi khusus untuk masa krisis sejak penghapusan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.Kerangka ini sangat dibutuhkan untuk beberapa hal sebagai berikut. 1. Penciptaan koordinasi antar tiga pengawas utama sistem keuangan yaitu Kementrian Keuangan (KK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi di masa yang akan datang juga akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 423 2. Menghadapi keterkaitan antar lembaga keuangan yang semakin kompleks dan kualitas pengawasan lembaga keuangan yang asimetrik.1 Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008, bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Sektor yang berperan sebagai penopang utama perekonomian adalah sektor keuangan. Kegagalan sektor keuangan memiliki implikasi yang buruk terhadap seluruh sistem keuangan (Stiglitz, 1994). Tabel 2 menjelaskan ruang lingkup pencegahan krisis oleh JPSK. Tabel 2. Ruang Lingkup Pencegahan Krisis JPSK Lingkup Krisis Solusi Bank mengalami kesulitan Pemberian Fasilitas Pembiayaan likuiditas yang dapat berdampak Darurat (FPD) oleh BI dengan sistemik jaminan pemerintah Bank mengalami kesulitan solvabilitas yang dapat berdampak sistemik FPD yang tidak dapat diluniasi menjadi beban APBN LKBB mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang dapat berdampak sistemik Tidak disebutkan Sumber: diolah dari Departemen Keuangan (2008) Permasalahan likuiditas bank dapat diselesaikan oleh pemegang saham sendiri atau melalui Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia. Peraturan mengenai FPJP telah diatur dalam: 1) UU BI Nomor 1 Bank Indonesia memiliki sistem pengawasan yang komprehensif, meliputi on- dan off-site supervision, di berbagai daerah di Indonesia. Kementrian Keuangan, melalui Bapepam-LK, belum memiliki sistem pengawasan sampai di daerah sedangkan Kementrian Koperasi belum memiliki sistem pengawasan lembaga keuangan. Kualitas pengawasan yang asimetrik menimbulkan insentif untuk masuk ke industri yang belum memiliki sistem pengawasan. 424 23 tahun 1999 dengan perubahan dalam UU Nomor 3 tahun 2004 pasal 11; 2) UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dengan perubahan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 37. Bank yang mengalami insolvabilitas namun tidak membahayakan sistem keuangan/perbankan diserahkan oleh LPS dengan dasar aturan UU BI Nomor 3 tahun 2004 dan UU LPS Nomor 24 tahun 2004. Rancangan JPSK yang telah ada beserta UU yang mendukung cenderung fokus pada kegagalan industri perbankan yang dapat berdampak sistemik. Mekanisme ini tidak sepenuhnya salah karena aset dan nilai kegiatan industri perbankan merupakan yang terbesar di sektor keuangan. Faktor bank-run, yang terjadi terhadap perbankan Indonesia di krisis tahun 1998, memberikan efek domino yang tidak optimal untuk situasi krisis. Namun demikian, perkembangan LKBB dan LKM yang pesat patut dimasukkan dalam model penanganan krisis. Bagaimanapun juga, keterkaitan antar lembaga keuangan telah erat dan paparan terhadap risikocontagion menjadi tinggi. 1. Aspek Legal Pengambil kebijakan telah memiliki berbagai peraturan pendukung pelaksanaan JPSK. Peraturan tersebut meliputi Perpu Amandemen UU BI, Perpu Amandemen UU LPS, serta harmonisasi UU terkait. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia fokus pada beberapa aspek sebagai berikut Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Fasilitas ini jarang digunakan oleh bank karena dapat mendapatkan dana di PUAB dan dapat memanfaatkan mekanisme Repo SUN/SBI. Perpu Nomor 2 tahun 2008 memperluas agunan melalui aset kredit kolektibilitas dan nilai agunan dijamin penuh sesuai yang disyaratkan. Bank Indonesia menetapkan Pengaturan Pelaksanaan (PBI) yang meliputi: 1. Penetapan kriteria agunan dan persyaratan CAR positif 2. Penempatan bank dalam pengawasan khusus sebagai upaya monitoring perbaikan manjemen likuiditas bank dan mencegah moral hazard. 425 Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS menetapkan perubahan nilai penjaminan untuk mengakomodasi potensi krisis terhadap perbankan seperti bank run. Perubahan nilai penjaminan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang dilaporkan kepada DPR. Nilai penjaminan tersebut dapat disesuaikan kembali setelah situasi krisis mereda. Peraturan JPSK juga perlu melakukan harmonisasi dengan UU yang lain. Undang-Undang yang terkait meliputi UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU LPS, UU LKBB, UU Keuangan Negara, UU APBN, dan UU SUN. Undang-Undang yang telah ada sebagian besar disusun untuk sitasi perekonomian normal. Kebutuhan pengembangan UU untuk mengakomodasi skenario krisis sangat krusial.Aspek legal JPSK juga perlu memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (JPSK) dalam model penanganan krisisnya.Tabel 3 menjelaskan keterkaitan UU tersebut dengan JPSK (Departmen Keuangan, 2008). Tabel 3. Harmonisasi Undang-Undang dengan Peraturan JPSK Undang-Undang Harmonisasi UU Bank Indonesia dan UU Perbankan Terbatas pada pengaturan dan pengawasan perbankan dalam sitasi normal. Peraturan JPSK perlu melengkapi UU tersebut dengan penanganan permasalahan bank berdampak sistemik dan penanganan industri perbankan pada situasi krisis. UU LPS Peraturan JPSK mengamanatkan pembentukan komite penyerahan bank gagal kepada LPS untuk ditangani sesuai UU LPS 426 UU terkait LKBB Terbatas pada pengaturan dan pengawasan LKBB dalam sitasi normal. Peraturan JPSK perlu melengkapi UU tersebut dengan definisi kesulitan yang dialami LKBB dan penanganan LKBB yang dapat berdampak sistemik. Peraturan JPSK juga perle melengkapi UU dengan penanganan LKBB dalam situasi krisis. UU Keuangan Negara dan UU APBN Peraturan JPSK perlu melengkapi UU dengan mekanisme penggunaan dana APBN untuk keadaan darurat yang tidak memerlukan persetujuan oleh DPR. UU SUN Peraturan JPSK perlu menetapkan penerbitan SUN dan surat berharga negara lainnya yang secara khusus dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan krisis. Sumber: modifikasi dari Departemen Keuangan (2008) Peraturan JPSK juga perlu mempertimbangkan kewenangan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khususnya ketua, dalam mengambil keputusan. Ketua KSSK memiliki experience, SDM, serta policy tools untuk mencapai objective penanganan krisis. Keputusan dibuat oleh KSSK dalam keadaan krisis jauh lebih baik dibandingkan tidak mengambil keputusan sama sekali. Tepat atau tidaknya suatu keputusan di situasi krisis tidak dapat menjadikan pertimbangan pengambil keputusan benar atau salah secara hukum. Oleh karena itu, Peraturan JPSK perlu memberikan perlindungan hukum terhadap anggota KSSK yang mengambil keputusan di situasi krisis. 427 2. Elemen Resolusidan Tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan Keputusan terkait desain JPSK yang optimum memerlukan studi khusus. Namun demikian, desain JPSK paling tidak harus mempertimbangkan fakta bahwa sektor keuangan tidak lagi terdiri dari bank dan lembaga keuangan non-bank saja. Sektor keuangan juga terdiri dari lembaga keuangan mikro baik dalam bentuk bank maupun koperasi. Tentu, masing-masing industri memiliki sensitivitas yang berbeda pada saat krisis perekonomian. Oleh karena itu, desain JPSK yang optimum perlu mempertimbangkan hal tersebut. Sistem JPSK paling tidak memiliki dua elemen utama yaitu resolusi untuk lembaga keuangan berdampak sistemik serta resolusi untuk lembaga keuangan berdampak minimum (Gambar 8). Lembaga keuangan berdampak sistemik adalah perbankan karena merupakan lembaga intermediasi utama dalam perekonomian. Lembaga keuangan berdampak minimum tetap akan memberikan adverse effect kepada perekonomian pada saat krisis, namun, dampaknya tidak sistemik seperti layaknya bank. Gambar 8. Elemen Utama JPSK Kedua elemen akan memiliki resolusi yang identik namun demikian resolusi lembaga keuangan berdampak sistemik tentunya akan sangat berbeda. Lebih dari itu, resolusi untuk lembaga keuangan berdampak sistemik memiliki implikasi hukum dan anggaran yang lebih kompleks. 428 Resolusi lembaga keuangan berdampak minimum seperti LKM patut disusun karena distribusi nasabah yang cenderung masyarakat menengah ke bawah. Tentunya pengambil kebijakan tidak ingin kelas masyarakat tersebut mendapatkan dampak ganda dari krisis yaitu kejutan terhadap harga dan aset di lembaga keuangan. Desain JPSK yang optimal juga perlu mengepankan resolution objectives sebagai fondasi pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Green dkk. (2011) menjelaskan bahwa otoritas pengaman sistem keuangan perlu mempertimbangkan objectives sebagai berikut: 1. Memastikan keberlanjutan jasa sektor keuangan vital 2. Menghindari adverse effects krisis terhadap stabilitas keuangan 3. Melindungi dana masyarakat 4. Melindungi deposan yang terasuransi. Resolution objectives tersebut kemudian diturunkan menjadi policy measures yang applicable untuk permasalahan nyata. Tentunya, JPSK di Indonesia akan memiliki resolution objectives yang berbeda, studi lebih lanjut sangat dikedepankan untuk menjawab hal tersebut. 3. Aspek Koordinasi Pengawas Sistem Keuangan Salah satu instrumen vital pencegahan krisis adalah penciptaan koordinasi yang juga meliputi data sharing dan data interfacing antar pengambil kebijakan. Koordinasi antar lembaga akan menciptakan measures yang vital untuk stabilitas sistem keuangan. Koordinasi juga mengurangi asymmetric information antar lembaga yang berpotensi menciptakan arogansi sektoral (turf wars), pengalihan tanggung jawab (pass the bucket), dan blame disbursement strategy (pengalihan wewenang/pengalihan kesalahan). Hasil eksperimen Rimawan dkk. (2011), dengan subjek penelitian civitas akademika Universitas Gadjah Mada, menjelaskan kenyataan bahwa koordinasi adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Koordinasi antar subjek hanya terjadi sebesar 2% saja untuk keseluruhan eksperimen. Hasil ini jauh lebih rendah dibandingkan hasil eksperimen mengenai koordinasi di negara 429 maju yang mencapai 40%. Oleh karena itu, koordinasi di Indonesia tidak bisa disusun hanya satu waktu saja, namun, harus bertahap. Koordinasi bertahap bertujuan untuk memunculkan reciprocity dan mutual trust. Koordinasi paling tidak dibangun dengan mempertimbangkan dua hal yaitu tahapan koordinasi dan bentuk komite koordinasi. Pertama, koordinasi optimum dibentuk untuk tiga tahapan yaitu koordinasi rutin di keadaan normal, koordinasi intensif di keadaan transisi, dan koordinasi komprehensif di keadaan krisis. Koordinasi rutin situasi normal bertujuan untuk menciptakan knowledge sharing, ikatan koordinasi, dan kerjasama antar lembaga pengawas. Kedua, komite koordinasi harus terdiri dari SDM yang sama dari setiap lembaga pengawas. SDM yang sama ini bertujuan untuk minimisasi loss of information pada saat koordinasi. Platform koordinasi sedimikian rupa bertujuan untuk meminimisasi biaya koordinasi dan akuntabilitas penetapan dan pengambilan kebijakan, khususnya di situasi krisis. Gambar 9 menjelaskan skema koordinasi antar lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).2 Koordinasi umum antar lembaga pengawas harus dimulai dengan penetapan peraturan mengenai fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam keadaan normal, transisi, dan krisis. Koordinasi harus dijalankan dalam basis harian melalui data sharing dan data interfacing untuk optimasi informasi antar industri di sektor keuangan yang semakin terkait. 2 Asumsi Bapepam-LK telah bergabung menjadi OJK dan pengawasan sementara perbankan dipegang oleh Bank Indonesia sampai sistem pengawasan OJK telah terbangun solid. 430 Gambar 9. Skema Koordinasi antar Lembaga Pengawas Pelaksanaan beserta detail teknis kerjasama saat ini telah diatur oleh perjanjian antar lembaga pengawas sektor keuangan. Sebagai contoh, kerjasama Bank Indonesia dan LPS diatur dalam SKB No. 11/55/KEP. GBI/2009 dan KEP/026/DK/X/2009 pada Oktober 2009. Kesepatakan ini mengatur koordinasi dan pertukaran data serta informasi untuk mendukung pelaksanaan kerja BI dan LPS. Koordinasi yang dibangun oleh BI dan LPS antara lain: 431 1. Implementasi jaminan pinjaman 2. Penanganan masalah perbankan 3. Resolusi bank gagal 4. Tindak lanjut terhadap bank yang perizinan telah dicabut 5. Pembahasan klaim penjaminan 6. Koordinasi data dan informasi Kerjasama BI, LPS, dan Kementrian Keuangan saat ini terangkum dalam MoU yang disepakati tanggal 30 Juli 2010. Kesepakatan ini merupakan langkah koordinasi untuk mencegah dan memberikan resolusi terhadap ancaman stabilitas sistem keuangan. Kesepakatan ini penting untuk menjaga momentum koordinasi di saat legislatif belum menyetujui UU JPSK. Kesepakatan antara ketiga lembaga tersebut meliputi: 1. Pertukaran data dan informasi oleh BI, LPS, dan Kementrian keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan 2. Pembahasan rutin terkait hasil monitoring keadaan sistem keuangan 3. Pemberian input teknis dan memastukan pengertian terhadap tindakan yang perlu dilakukan masing-masing lembaga untuk menjaga stabilitas 4. Implementasi simulasi dan evaluasi menggunakan protokol manajemen krisis. (BI, 2011). Salah satu output dari memorandum ketiga lembaga pengawas di atas adalah protokol manajemen krisis. Protokol ini adalah subset kerjasama yang khusus memberikan panduan terkait parameter di periode krisis. Protokol ini mencakup pencegahan krisis sektor perbankan, resolusi krisis, dan koordinasi monitoring dan resolusi krisis (BI, 2011). Ketiga lembaga pengawas ini, ke depannya, diharapkan mampu menciptakan indikator deteksi krisis atau early warning system sebagai komplemen dari indikator macroprudential yang telah ada. Sekali lagi, protokol krisis ini juga perlu mengedepankan pentingnya perlindungan legal terhadap pengambil kebijakan penting pada masa krisis (Abimanyu, 2009). 432 4. Komite Stabilitas Sistem Keuangan Beberapa negara telah mengedepankan pentingnya komite untuk membahas isu penting terkait pelaksanaan pengawasan lembaga keuangan. Pembahasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengupayakan knowledge sharing, data sharing dan interfacing, serta simulasi pengambilan keputusan terutama di waktu krisis. Tabel 4 menjelaskan bahwa komite di berbagai negara terdiri dari bank sentral, Kementrian Keuangan, dan otoritas pengawas lembaga keuangan bank dan nonbank. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan integrasi pengambilan kebijakan oleh BI, LPS, Kementrian Keuangan, dan nantinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia dan LPS dalam KSSK memiliki tugas untuk menetapkan penanganan likuiditas dan solvabilitas bank bermasalah yang memiliki dampak sistemik. Kedua lembaga tersebut juga memiliki tugas untuk memberikan resolusi terhadap bank yang telah gagal. Bank Indonesia, khususnya, akan terus melaksanakan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sebagai bank sentral Indonesia (Bank Indonesia, 2007). Tabel 4. Harmonisasi Undang-Undang dengan Peraturan JPSK Negara Anggota Komite Ketua Britania Raya Bank of England, Financial Services Authority, Kementrian Keuangan Kementrian Keuangan Amerika Serikat Kementrian Keuangan, Federal Reserve, Security Exchange Commission, dan Federal Deposit Insurance Corporation Kementrian Keuangan Australia Kementrian Keuangan, Reserve Bank of Australia, dan Australia Prudential Regulatory Authority Kementrian Keuangan 433 Jepang Kementrian Keuangan, Bank of Japan, dan Financial Services Authority Kementrian Keuangan Singapura Kementrian Keuangan dan Monetary Authority of Singapore Kementrian Keuangan Sumber: Kementrian Keuangan (2008) Kementrian Keuangan bertindak sebagai ketua KSSK di berbagai negara. Posisi ini merupakan langkah strategis komite stabilitas karena Kementrian Keuangan memiliki koordinasi langsung dengan pengambil kebijakan di pemerintah. Bank sentral dan otoritas pengawas jasa keuangan akan optimal jika bertindak sebagai anggota karena independensi mereka dalam pelaksanaan pengawasan harus terjaga. Hal ini penting untuk menjaga independensi serta kualitas input bank sentral dan otoritas pengawas jasa keuangan dalam komite stabilitas. Komite yang optimal untuk kasus di Indonesia paling tidak dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait penyusunan kebijakan oleh KSSK serta terkait resolusi bank bermasalah dengan dampak sistemik yaitu Komite Koordinasi (KK). Gambar 10 menjelaskan bahwa Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai KSSK dalam tataran pengambilan kebijakan. Skema koordinasi pengambilan kebijakan KSSK tidak mengikutsertakan LPS sebagai upaya menghindari moral hazard. Namun, KSSK tetap menerima masukan dari LPS dalam pelaksanaan tugas koordinasinya. 434 Gambar 10. Skema Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Komite Koordinasi Peran Kementrian Keuangan sebagai ketua KSSK memiliki berbagai pertimbangan khusus yang meliputi dampak sistemik, risiko fiskal, serta akuntabilitas fiskal (Kementrian Keuangan, 2008). Ketiga aspek tersebut mempertimbangkan biaya koordinasi dengan pemerintah untuk keputusan penting di saat krisis. Selain itu, Kementrian Keuangan memiliki otoritas untuk menghitung risiko fiskal dan menetapkan besaran fiskal untuk menangani permasalahan di saat krisis. Kementrian Keuangan dalam hal 435 ini sebaiknya mengambil kebijakan tanpa harus meminta persetujuan kepada DPR karena akan menimbulkan lag dalam pengambilan keputusan strategik. Komite Koordinasi merupakan wadah untuk membahas resolusi terhadap bank yang dianggap bermasalah dan berdampak sistemik oleh KSSK. Komite ini memberikan wewenang kepada LPS untuk melaksanakan fungsi resolusinya terkait bank bermasalah. Skema Komite Koordinasi ini memberikan independensi serta keleluasaan kepada LPS untuk menjalankan tugasnya dalam resolusi perbankan. Namun, keberadaan KK harus segera didukung oleh suatu kerangka hukum yang pasti untuk menghindari moral hazard. 5. Koordinasi Fiskal Moneter Kebijakan fiskal dan moneter merupakan elemen kebijakan ekonomi makro yang memiliki keterkaitan erat. Kebijakan fiskal mencakup pengaturan perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi agregat. Variabel utama dalam kebijakan fiskal meliputi defisit pemerintah, utang, tingkat pajak, serta tingkat pengeluaran. Kebijakan moneter, di sisi lain, mengatur ketersediaan kredit dengan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah stabilitas harga, namun, kebijakan moneter juga dapat digunakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal di Indonesia dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kedua lembaga ini menjalankan tugasnya independen satu dengan lainnya, walaupun demikian, implikasi kebijakan fiskal dan moneter tidaklah independen. Implikasinya adalah keterkaitan antara kebijakan fiskal dan moneter sehingga kedua lembaga ini perlu menciptakan suatu kerangka koordinasi. Koordinasi ini penting karena kedua lembaga memiliki tujuan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan peningkatan lapangan kerja. Koordinasi kedua lembaga juga harus mempertimbangkan 436 kenyataan bahwa arah salah satu kebijakan memiliki dampak yang berlawanan bagi tujuan kebijakan lembaga lain. Kebijakan fiskal discretionary mempengaruhi kebijakan moneter melalui dua jalur yaitu jalur langsung dan jalur tidak langsung (Gambar 10). Jalur langsung meliputi dampak defisit fiskal dan pajak terhadap inflasi serta dampak fiskal terhadap suku bunga pasar. Jalur tidak langsung meliputi asa pelaku pasar terhadap outome dari suatu kebijakan fiskal pemerintah. Ekspansi fiskal pemerintah yang meliputi peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan defisit anggaran. Peningkatan pengeluaran juga dapat disebabkan oleh status quo kebijakan yang tidak strategis seperti kebijakan subsidi.3 Pilihan kebijakan untuk membiayai defisit anggaran antara lain pencetakan uang baru oleh otoritas serta peningkatan target pemasukan pajak. Pilihan pencetakan uang menyebabkan jumlah uang beredar meningkat dan nilai riil uang turun akibat inflasi. Pilihan ini memang tidak lagi preferable bagi pengambil kebijakan di dunia, namun, kebijakan ini akan dilakukan sebagai desperate measure. Pilihan yang feasible adalah peningkatan target pajak dari barang konsumsi melalui pajak penjualan. Peningkatan harga akibat kebijakan ini tentu memiliki adverse effect terhadap stabilitas harga. 3 Kebijakan subsidi energi, misalnya, membengkak Rp90 triliun dari Rp160 triliun menjadi Rp250 triliun pada tahun 2011. Implikasinya adalah peningkatan defisit anggaran dari yang telah ditetapkan sebesar Rp125 triliun di RAPBN 2011. 437 Gambar 11. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Outcome Kebijakan Moneter Pembiayaan defisit fiskal juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar keuangan melalui instrumen surat utang negara. Pembiayaan melalui mekanisme ini menjadi salah satu pilihan utama pemerintah Indonesia saat ini, relatif terhadap pengajuan utang luar negeri baru. Kebijakan penerbitan surat utang memiliki dampak terhadap suku bunga di pasar yang memiliki implikasi terhadap suku bunga kredit. Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi outcome kebijakan moneter melalui jalur permintaan agregat. Peningkatan gaji publik meningkatkan konsumsi agregat yang memiliki implikasi inflasi karena penawaran agregat inelastis di jangka pendek. Keadaan ini berpotensi terjadi di Indonesia karena belanja gaji cukup tinggi dan rencana kenaikan gaji pokok sebesar 10% di tahun 2012. Implikasi kebijakan fiskal berupa inflasi dan perubahan suku bunga kredit akan mempengaruhi kebijakan moneter secara tidak langsung, yaitu melalui asa. Outcome kebijakan fiskal bisa dianggap sebagai kejutan terhadap planning yang telah dilakukan pelaku pasar sehingga mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga serta perilaku produksi dan penetapan harga oleh perusahaan. 438 Perlu ada upaya untuk membangun koordinasi fiskal-moneter di Indonesia antara Pemerintah melalui Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga tanpa mengorbankan tujuan dari masing-masing lembaga (Abimanyu, 2010). Tujuan ini juga sejalan dengan fungsi Bank Indonesia dalam pengawasan makroprudensial serta Kementrian Keuangan dalam penetapan UU sektor keuangan. Tabel 5. Aspek Koordinasi Fiskal Moneter Koordinasi Fiskal Moneter Dasar Hukum Penetapan Target Inflasi oleh Kemenkeu dan Pelaksanaan oleh BI UU BI Penyampaian indikator ekonomi makro dan kebijakan moneter oleh BI UU BI Penyampaian sasaran ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahunan serta dampak moneter, sektor riil, dan valas dari postur APBN UU KN Koordinasi kebijakan penerbitan surat utang negara UU SUN Penerbitan dan Pencetakan Mata Uang UU Mata Uang Pengelolaan Kas Pemerintah UU Perbendaharaan Negara Koordinasi Kerjasama Keuangan Internasional dalam ASEAN, ASEAN+3, Bank Dunia, IMF, ADB, IDB, dan G20 Koordinasi fiskal moneter ini sedikit berbeda dengan koordinasi dalam kerangka KSSK.Koordinasi dalam keadaan ekonomi normal merupakan upaya untuk meningkatkan probability of success dari setiap 439 tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah.Tujuan tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar rupiah.Beberapa kebijakan fiskal, seperti dijelaskan sebelumnya, memiliki adverse effect terhadap inflasi.Kementrian Keuangan perlu melakukan koordinasi sehingga Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk mengakomodasi dampak buruk tersebut. D. Diskusi Sektor keuangan yang kuat merupakan fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.Namun demikian, sektor keuangan sensitif terhadap gejolak ekonomi internal maupun eksternal.Jaring pengaman sistem keuangan adalah kerangka yang memiliki peran signifikan terhadap stabilitas di sektor keuangan.Kerangka ini tidak hanya memberikan landasan hukum terhadap pengawasan dan penanganan sektor keuangan di saat krisis namun juga membentuk asa pelaku ekonomi, baik rumah tangga dan perusahaan. Kerangka JPSK juga harus mencakup kerangka kerja dan kerangkan hukum KSSK dan juga Komite Koordinasi.Kedua komite tersebut sangatlah penting terutama koordinasi di masa krisis dan penanganan lembaga keuangan, khususnya bank, yang bermasalah.Independensi pengambilan kebijakan serta keleluasaan untuk membuat keputusan tanpa perlu melapor pada legislatif merupakan elemen penting dalam kerangka komite.Komite Koordinasi juga perlu memperdalam berbagai skenario resolusi penanganan bank yang bermasalah yang optimal. Koordinasi fiskal moneter merupakan elemen penting pendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah dalam keadaan normal. Pencapaian inflasi, misalnya, tidak akan optimal jika Kementrian Keuangan tidak melakukan koordinasi terkait kebijakan fiskal yang akan ditempuh dalam suatu periode. Bank Indonesia dapat menentukan berbagai skenario kebijakan moneter sebagai countermeasure dari dampak kebijakan fiskal tersebut. Persiapan ini memberikan ruang pembentukan asa kepada Bank Indonesia dan pelaku ekonomi mikro. 440 Referensi Abimanyu, 2009, “Model-Model Penditeksian Dini Krisis Ekonomi,” BPFE-UGM Yogyakarta, 2009. Abimanyu, 2010, “Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal,” Gramedia Jakarta, 2010. Ashari, 2006, “Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya,” Analisis Kebijakan Pertanian, 4:2, hal. 146-164, diakses Juni 2010 dari pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART4-2c.pdf. Bank Indonesia, 2007, Booklet Perbankan Indonesia 2007,Vol. 4. ____________, 2007, Booklet Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. ____________, 2009, Laporan Pengawasan Perbankan 2008, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbanka n+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Pengawasan+Perbankan/ LPP_2008_17042008.htm ____________, 2010a, Laporan Keuangan Publikasi Bank, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+ Keuangan+ Publikasi+Bank/Bank/Bank+ Umum+ Konvensional/ ____________, 2010b, Laporan Pengawasan Perbankan 2009, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+ Stabilitas+Keuangan/Laporan+Pengawasan+Perbankan/lpp_2009. htm ____________, 2011, Financial Stability Review 2011, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Bapepam-LK, 2009, Laporan Tahunan 2008, diakses Mei 2010 dari http:// www.bapepam.go.id/bapepamlk/annual_report/AR-BAPEPAMLK_2008.pdf 441 Bapepam-LK, 2010, “Pengawasan Lembaga Keuangan,” diakses Mei 2010 dari http://www.bapepam.go.id/p3/index.htm Departemen Keuangan, 2008, Penjelasan Pemerintah Dalam Rangka Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2,3,4 Tahun 2008, diunduh dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q= kementrian%20keuangan%20komite%20stabilitas%20sistem%20 keuangan%20filetype%3Apdf&source=web&cd=3&ved=0CC4QF jAC&url=http%3A%2F%2Fwww.depkeu.go.id%2Find%2FData% 2FBerita%2Fpenjelasan_pemerintah.pdf&ei=RxAFT4PmLMrHrQ eN4vneDw&usg=AFQjCNGjN3UxO_uq8St7TJ1fmUoAhRsG4g. Departemen Keuangan, 2010, “Data Pokok APBN 2005-2010,” diunduh Agustus 2010 dari www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/data pokok-ind2010.pdf. International Monetary Fund (2011), International Financial Statistics 2011, diunduh dari www.imf.org. Nier, E.W., 2009, “Financial Stability Frameworks and The Role of Central Banks: Lessons From the Crisis,” International Monetary Fund Working Paper, 09/70, diakses Mei 2010 dari http://www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2009/wp0970.pdf Pegadaian, 2010, Laporan Tahunan 2009, diakses Mei 2010 dari http:// www.pegadaian.co.id/k.annual.php?uid= Pradiptyo, R., B. Sasmitasiwi, G.A. Sahadewo, R. Rokhim, M. Ulpah, dan I.A.A. Faradynawati (2010), Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, Tim Kerjasaa Penelitian FEB UGM dan FE UI. Pradiptyo, R., B. Sasmitasiwi, G.A. Sahadewo (2011), “A Bridge Too Far; The Strive to Establish A Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia,”mimeo. 442 INDEKS Asa nalar 7, 141, 144, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 190, 259 Asa yang adaptif 151, 152, 153, 154 Aset bubble 360 Asia financial crises 121 Balances budget 369 Bank run 35, 122, 182, 309, 374, 376, 377, 426 Basel 213, 320, 343, 344, 403, 408 BI rate 33, 105, 181, 206, 213, 216, 288, 294, 296, 354, 355 Bilateral Swap Arrangements 407 Budget deficit 112, 122, 162, 164, 166, 398, 401, 403, 405 Built-in stabilizer 346 Chiang Mai Initiative 10, 407 Computable general equilibrium 8, 194, 213, 223 Consultative Group on Indonesia 371 Contigency plan 48, 63, 64, 72, 73, 74 Convertible currency 392 Crawling peg 25 Credit crunch 320, 333, 347, 363, 404 Crowding out 36, 45, 143, 399 Currency appreciation 121, 395 Decoupling 47 De Javasche Bank 15, 366, 367 Depresiasi 28, 178, 179, 199, 373, 415 Dewan Moneter 2, 3, 9, 16, 17, 19, 21, 29, 45, 46, 58, 93, 228, 229, 249, 252 Early Warning System 38, 432 Ekspansi moneter 8, 22, 160, 194, 200, 213 Exchange rate management 396 Export-led growth strategy 392 External shock 64 Financial cycle 327 Financial imbalances 338, 360 Financial Safety Net 32, 407 Financial Stability Index 38, 265 Fiscal sustainability 51, 92, 119, 130, 135, 137, 140 443 Forum Stabilitas Sistem Keuangan 38, 73, 229 Forward looking expectations 153 Full employment 143, 164 Granger causality test 128, 129 Great Depression 413 Great Moderation 324 Gunting Syafrudin 367 Holding period 297, 348, 396 Hyper inflation 84, 90, 368 Imported inflation 414 Indeks Keyakinan Konsumen 294 Inflation targeting framework 53, 105, 111, 114, 131, 134, 135, . 136, 181, 324, 325, 326, 350, 351 Insentif fiskal 8, 194, 217, 220, 386 Institutions 310, 311, 344 Jaring Pengaman Sistem Keuangan 10, 34, 37, 74, 75, 302, 319, 377, 390, 413, 418, 423, 424, 428, 440 Kapitalisasi pasar 290 Kebijakan countercyclical 195 Kebijakan diskresi 235 Kebijakan fiskal eksogen 9, 244, 245, 249 Kebijakan moneter akomodatif 198 444 Kesinambungan fiskal 66, 67, 217, 230 Klasik Baru 152 Komite Stabilitas Sistem Keuangan 314, 418, 427, 433, 435 Kontraksi ekonomi 193 Kredit Usaha Rakyat 204 Krisis keuangan global 1, 3, 4, 5, 9, 35, 42, 193, 195, 196, 197, 204, 207, 208, 220, 309, 354, 425 Kurva Phillips 155, 174, 234 Leaning againts the wind 339 Letter of Intent 372, 374 Liquidity support 112, 122, 123, 130, 133 Maastricht Treaty 59, 163 Makroprudensial 10, 270, 298, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 314, 317, 318, 319, 323, 326, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 439 Macroprudential 1, 3, 36, 39, 302, 307, 311, 316, 320, 363, 364, . 432 Macrosurveillance 316, 318 Managed float 25, 121, 396, 397 Market clearing 152 Model koreksi kesalahan 144, 160 Monetary dominance 6, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 130 Nash Equilibrium 50, 52, 91, 92 Neoklasik 143 Net domestic assets 96 Net foreign assets 96, 122 New Keynesian 81, 151, 163, 174, 233, 234, 235, 259, 260 Non-core depositnya 270 Off-budget account 118 Open market operation 23, 123, 403 Otonomi daerah 5, 47, 56, 57, 58, 67, 78, 184 Otoritas Jasa Keuangan 38, 39, 302, 356, 423, 426, 430, 433 Output gap 90, 233, 339, 351 Overheating economy 104 PAKJUN 23, 371 Paradox of growth 47 Pelarian modal asing 74, 373 Permintaan agregat 8, 43, 54, 57, 58, 61, 143, 174, 194, 196, 197, 198, 206, 214, 215, 216, 217, 220, 230, 234, 235, 236, 352, 438 Perfect foresight 154 Phillip Curve 48 Policy mix 14, 48, 50, 52, 82 Policy rule 53, 173, 174, 256, 261, 262 Prime rate 44 Prosiklikalitas 326, 327, 328, 331, 332, 334, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 352, 355, 360 Prudential policy 302, 307, 310, 320, 363, 364 Public debt 113, 114, 134, 135, 140, 162, 188, 262 Quasi fiscal activities 6. 111, 112, 114, 116, 118 Quasi fiscal deficit 65, 117, 122 Quantitative easing 195, 292, 293, 400 Reformasi perpajakan 370 Resesi 23, 43, 44, 49, 50, 53, 85, 87, 90, 106, 235, 252, 343 Ricardian Equivalence 93, 142, 166, 198 Rime-inconsistency 48 Risiko sistemik 74, 197, 202, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307. . 308, 310, 111, 312, 316, 318, 360, 362 Risk based supervision 317 Rules-based frameworks 53 Sanering 85, 367 Seigniorage 118, 125, 130, 132, 177 Social lost 103, 107 Sovereign Welfare Fund 64 Stabilisasi harga 57, 181, 227, 230, 251, 377, 386, 387 Stabilitas sistem keuangan 37, 38, 39, 73, 206, 229, 298, 301, 445 302, 303, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 338, 339, 341, 353, 355, 357, 369, 362, 418, 424, 427, 429, 432, 433, 435, 441 Stimulus fiscal 193, 213 Steady state 234, 241 Subprime mortgage 13 Surat Perbendaharaan Negara 65 Systemic risk regulator 311 Systemically Important Financial 310, 311, 344 Taylor Rule 174, 245, 246, 260, 350 Time consistentcy 235 Transmisi kebijakan moneter 47, 176, 351, 353, 360, 361 Uang primer 7, 95, 96, 97, 179, 180, 188 Undervaluation 391, 394, 395, 406 446