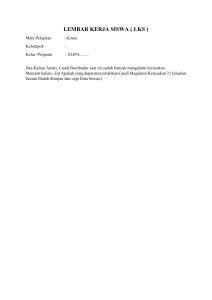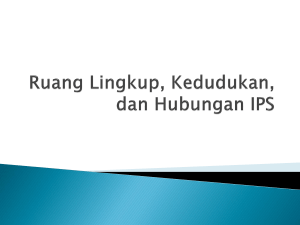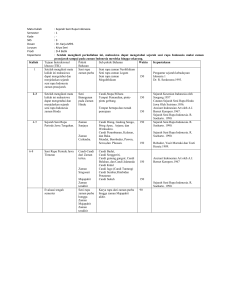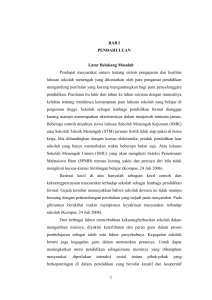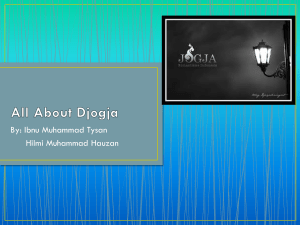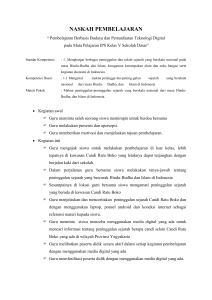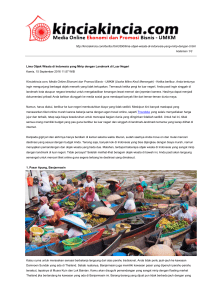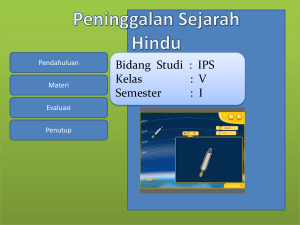tata cara pendirian candi: perspektif negarakertagama
advertisement

TATA CARA PENDIRIAN CANDI: PERSPEKTIF NEGARAKERTAGAMA Dwi Budi Harto ∗ Abstrak Pendirian candi di Indonesia khususnya Jawa sebagian besar masih dalam keadaan ‘kelabu’, hal ini disebabkan terbatasnya data arkeologis yang terkait dengan pendirian dan tata bangun candi. Data lama dan pendapat sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa candi adalah makam raja dan kerabatnya, ternyata hal ini tidak benar. Negarakertagama sebagai data arkelogis menduduki urutan kedua (bahkan bisa pertama) tingkat validitasnya bila dikorek datanya terkait dengan tata cara pendirian candi, maka akan menggambarkan tata cara pendirian candi yaitu pada peristiwa Sradha Agung Sri Rajapatni. Di samping menggunakan kitab Negarakertagama tata cara pendirian candi ini akan didasarkan pula pada data-data lain sebagai acuan pembahasan. Data lain yang digunakan sebagai acuan misalnya seni bangun/arsitektur candi, bahasa rupa relief candi, hasil kajian ikonografis, dan lain-lain. Berdasarkan datadata tersebut terlihat bahwa pendirian candi di Jawa sangat memperhatikan hubungan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos yang didasarkan atas sistem religi Hindu. Dengan kata lain, pendirian candi saat itu sangat kosmologis, yang jarang dijumpai pada konsep pembangunan gedung di masa sekarang ini. Kata kunci: Negarakertagama, kosmologi, makrokosmos, mikrokosmos, candi, master plan candi. Pendahuluan Siapakah yang membuat candi-candi di Indonesia pada masa Hindu-Budha dan bagaimana tata cara pembuatannya? Pertanyaan ini sampai kini belum mendapat jawaban yang memuaskan. F.D.K. Bosch (dalam Suru 1983: 85) berpen-dapat bahwa para pelaksana pembuatan candi-candi itu adalah orang-orang Indonesia sendiri, dan mereka berpegang pada kitab-kitab tuntunan yang disebut Çilpasastra, yang merupakan buah karya orang India. Di dunia seni bangun Hindu khususnya dalam pembuatan bangunan-bangunan suci sedapat mungkin mengikuti pedoman-pedoman yang terdapat dalam kitab-kitab petunjuk, seperti misalnya kitab Çilpasastra itu. Walaupun di Indonesia belum pernah ditemukan Çilpasastra tersebut, tetapi aturan-aturan pembuatan candi ini tampaknya diturunkan secara lisan sehingga tidak pernah sampai kepada generasi sekarang (Bosch 1924: 6 - 41, 26 dalam Santiko 1987:77). Pendapat ini didasarkan pada kesesuaian antara jenis-jenis bingkai (pelipit), pilaster-pilaster serta ukuran pada candi-candi tua di Jawa Tengah dengan uraian Çilpasastra (Vastusastra) terutama kitab Manasara (Santiko 1995:7). Pada ∗ umumnya para arsitek patuh Penulis adalah magister seni dan dosen Seni Rupa FBS Universitas Negeri Semarang 1 mengikuti pedoman-pedoman yang termuat dalam kitab-kitab tersebut, tetapi lama kelamaan mereka makin membebaskan diri. Bangunan-bangunan candi di Indonesia, makin lama makin mengandung unsur Indonesia (Suru 1983: 86). Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa latar belakang penciptaan candi adalah untuk makam raja atau kerabatnya, bahkan mata pelajaran Sejarah di SMP dan SMA juga mengatakan demikian. Kebenaran tentang pendapat ini sangat terkait dengan tata cara pendirian candi. Membahas tata cara pendirian candi sebagian ahli menggolongkannya pada kajian arkeologis, tetapi sebenarnya hal ini secara integral masuk dalam pengetahuan tentang sejarah kesenian khususnya sejarah seni rupa. Oleh karena itu pembahasan sejarah seni rupa sering pula melibatkan data-data arkeologis sebagai pijakan. Pendapat mengenai candi sebagai makam, semula didasarkan pada etimologi bahwa kata candi berasal dari kata candikarga yang artinya rumah candika. Candika adalah nama dewi Durga. Dewi Durga adalah dewi penguasa jiwa, Dewi Maut atau dewi kematian. Dengan demikian pengertian candi adalah bangunan yang berhubungan dengan dewi Durga. Yang dikuburkan dalam bahasa Kawi disebut cinandi (Soekmono 1981:81). Kaitannya dengan Durga dan istilah cinandi inilah, akhirnya masyarakat menyebut candi sebagai makam. Terlebih lagi dengan ditemukannya pendaman abu yang dikuburkan pada pondasi atau dasar candi, sesuai dengan masa raja yang memerintah maka memperkuat pendapat masyarakat bahwa candi adalah makam raja. Selain itu pengertian candi sebagai makam karena juga terkait dengan pendapat masyarakat bahwa candi adalah cungkup. Sebutan cungkup oleh masyarakat awam identik dengan makam. Setelah mengadakan penelitian panjang untuk disertasinya, Soekmono (1977:241) menegaskan bahwa candi bukanlah makam, tetapi candi adalah bangunan kuil. Setelah diadakan uji laboratorium, berdasarkan temuan Soekmono, abu yang terdapat dalam peripih di dasar candi adalah abu binatang korban, bukan abu manusia (raja). Memang candi itu sebenarnya adalah bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khusus untuk para raja atau orang terkemuka. Menurut Yudoseputro (1993: 118), sebutan candi sebagai bangunan suci di India sendiri tidak dipakai. Sebagai bangunan kuil tempat menyelenggarakan upacara agama Hindu di India dikenal dengan sebutan vimanna yang berarti rumah dewa atau ratha yang berarti kendaraan dewa. Sedangkan untuk keperluan ibadah agama Budha di India dikenal dengan sebutan stupa atau çaitya, çaityagraha dan vihara. Di Indonesia bangunan suci Budha juga disebut candi. Itulah sebabnya mengapa sebutan candi di Indonesia menunjuk bangunan yang memiliki bermacam-macam fungsi. Ada candi yang berfungsi sebagai kuil Hindu, candi sebagai stupa dan bihara Budha, candi sebagai pintu gerbang, candi sebagai bale kambang (Yudoseputro 1993:118). Selain itu masih ada lagi sebutan untuk candi 2 yaitu candi pahatan misalnya di Gunung Kawi Bali (Yudoseputro 1993:123) atau sering disebut candi pertapaan/gua pertapaan seperti Gua Selomangleng di Kediri dan Tulungagung Jawa Timur (Yudoseputro 1993: 128; Santiko 1995:2). Analog dengan pemikiran ini mungkin tidak semua peninggalan seni bangun yang oleh awam disebut candi, dapat didefinisikan sebagai candi dalam artian yang benar secara etimologis (Suru 1983: 85). Pada akhirnya candi sering dipandang sebagai monumen atau bangunan peringatan dari raja yang meninggal (Yudoseputro 1993:118). Lebih lanjut Yudoseputro menjelaskan bahwa kebiasaan untuk mengabadikan kekuasaan raja bertolak dari alam pikiran memuja atau kultus raja, suatu alam pikiran yang bersumber pada kepercayaan lama dari kebudayaan Indonesia. Alam pikiran ini juga berpengaruh kepada pandangan mengenai arca dewa yang disimpan di kamar/bilik candi. Arca dewa itu juga dipandang sebagai perwujudan dari raja yang meninggal, suatu pandangan bahwa raja adalah titisan dewa (Yudoseputro 1993:118). Paham semacam ini oleh Subagya disebut paham dewaraja (Subagya 1981:79). Oleh karena itu sering terdengar ungkapan bethara ngejawantah, atau dalam ajaran Hindu dewa sering muncul dalam bentuk advaita, angsha, avatara, aradhana dan pratista, sebagai contoh Brahma dalam bentuk Ken Arok (Subagya 1981:79). Secara rinci alasan bahwa candi bukanlah makam raja, dapat diikuti pada uraian selanjutnya dan sekaligus terkait dengan uraian tentang tata cara pendirian candi di Indonesia atau di Jawa khususnya. Kosmologi Pendirian Candi Sistem Religi Hindu sebagai Latar Belakang Pendirian Candi Fungsi candi yang beragam sebagaimana diuraikan di atas, disebabkan oleh kesalahan masyarakat secara umum yang memberi label “candi” pada bangunan suci Hindu atau Budha. Oleh karena itu perlu dibahas latar belakang pendirian candi secara kosmologis. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang latar belakang pendirian candi sesuai dengan alam pikir masyarakat saat itu, bukan atas dasar konsep penciptaan candi berdasarkan teori yang berkembang untuk melatarbelakangi penciptaan karya seni saat ini, misalnya saja teori estetika formal (Barat) atau teori estetika berdasarkan pendapat sejumlah ahli estetika Barat. Berfikir kosmologis akan mengembalikan kedudukan candi pada kosmologinya. Kosmologi secara leksikal berarti: (1) cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta; (2) ilmu tentang asal-usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari, serta hubungan sistem matahari dengan jagad raya; (3) cabang dari metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3 1989:463). Istilah “kosmologi” ini tidak hanya digunakan pada bidang Astronomi [menunjuk arti leksikal (1) dan (2)], tetapi juga digunakan di bidang Antropologi, Arkeologi, dan ilmu budaya lainnya. Penggunaan istilah “kosmologi” pada teori-teori budaya ‘cenderung’ pada arti yang ketiga (walaupun tidak persis sama), yaitu: cabang dari metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan Purwanto (dalam Imajinasi, vol. 2 Januari 2005) sebagai berikut: “Kosmologi memiliki makna keteraturan, keseimbangan, dan harmoni yang manifestasinya adalah sistem alam semesta sebagai makrokosmos. Dalam sistem itu Tuhan ditempatkan sebagai pusat kosmos yang mengatur keseluruhan sistem tersebut. Dalam budaya Jawa, konsep kosmologi diimplementasikan pada elemen-elemen di alam semesta ini antara lain manusia, rumah, desa, dan komunitas lain sebagai mikrokosmos. Konsep kosmologis pada kehidupan budaya masyarakat Jawa adalah menyatunya makro dan mikrokosmos yang lebih populer disebut manunggaling kawula lan Gusti”. Terkait dengan pernyataan di atas, perlu dilacak bahwa masyarakat Jawa yang memiliki budaya Jawa telah mengalami serangkaian sejarah masa lalunya, sehingga dapat diidentifikasi kosmo-loginya. Kemunculan istilah manunggaling kawula lan Gusti bisa dilacak dari sejarah sistem religi ma-syarakatnya. Masyarakat Jawa sampai saat ini paling tidak mengalami masa lalu mulai dari Jaman Pra-sejarah, Hindu Budha, Islam, Kolonial, dan modern saat ini. Manunggaling kawula lan Gusti sebenarnya telah ada sejak masa Prasejarah dengan manifestasi roh nenek moyang yang berkedudukan di langit sebagai makrokosmos dan manusia di dunia sebagai mikrokosmos. Konsep ini diperkuat dengan da-tangnya kebudayaan Hindu Budha yang datang dari India. Dalam ajaran Hindu dikenal adanya 3 jaman yaitu: jaman Weda, jaman Brahmana, dan Upanisad. Jaman Weda keagamaan berkisar kepada pemu-jaan dewa (tenaga alam) guna mendapatkan keuntungan, dan dalam jaman Brahmana keagamaan berpusat kepada saji dan upacara saji yang menjadi monopoli kasta Brahmana, maka dalam jaman Upanisad ini keagamaan dibalikkan dari soal lahir menjadi soal batin (Soekmono 1981: 13). Pada jaman Upanisad ini agama cenderung bersifat filosofis. Munculanya pendapat manunggaling kawula lan Gusti pada masyarakat Jawa tampaknya bersumber dari jaman Upanisad ini. Karena, pada jaman Upanisad pemeluk agama Hindu memiliki cita-cita luhur/mulia yang secara filosofis adalah bersatunya atman dan Brahman. Brahman adalah zat abadi/kekal yang dapat diidentikkan dengan makrokosmos (jagad besar). Brahman ibarat kembang api besar yang memercik ke segala arah. Nyala Brahman sebagai kembang api lebih lama dibandingkan dengan percikannya. Percikan Brahman sebagai pusat/pangkal alam seisinya ini disebut atman. Atman mendapat bentuk yang nampak yaitu manusia, binatang, dan sebagainya (Soekmono 1981: 14). Atman dapat diidentikkan dengan mikrokosmos (jagad kecil). Dengan demikian pendapat manunggaling kawula lan Gusti dapat diturunkan dari sistem religi agama Hindu yaitu bersatunya atman dengan Brahman 4 sebagai cita-cita luhurnya. Dengan kata lain secara kosmologis sistem religi Hindu ini mendasarkan pada pandangan filosofis tentang bersatunya mikrokosmos (atman) dengan makro-kosmos (Brahman). Sistem inilah yang mendasari pendirian candi di Indonesia. Sejarah Kerajaan Majapahit sebagai Setting Pendirian Candi dan Validitas Datanya Latar/setting penulisan ini adalah sejarah Majapahit umum, karena data sejarah tentang tata cara pendirian candi pada masa yang lain (misalnya Mataram Kuno), tidaklah serinci masa ini. Masa Majapahit ini sering digolongkan para ahli sebagai masa candi-candi Jawa Timur. Sejarah Majapahit layak dijadikan setting pendirian candi karena pada masa ini banyak peninggalan candi dibanding masa kerajaan Jawa Timur yang lain (Kediri dan Singasari). Berdasarkan data sejarah, diketahui bahwa pada masa kerajaan Kediri dan Singasari cenderung lebih banyak menghasilkan karya sastra dibanding peninggalan candi. Di sisi lain bahwa pembangunan bangunan suci atau bangunanbangunan kerajaan lainnya cenderung subur apabila pemerintahan kerajaan tersebut aman, tenteram, dan damai. Sebagaimana diketahui dari data sejarah bahwa pada masa Hayam Wuruk (1351-1389 M) dengan patih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kondisi negara saat itu aman dan bahkan negara memiliki misi untuk ekspansi wilayah negara sampai ke wilayah Asia Tenggara (saat ini). Wajarlah bila pada masa Majapahit ini tumbuh subur bangunan candi juga peninggalan lainnya misalnya kitab (karya sastra), keramik terakota, kerajinan logam, dan lain-lain. Di sepanjang kota Trowulan (Mojokerto), Kediri, Blitar, Malang, dan Tulungagung banyak didirikan bangunan candi. Menurut Soekmono (1993:69-70) ada 4 jenis bangunan suci Hindu-Budha pada masa Majapahit yang terdapat dalam Negarakertagama, di antaranya: dharma haji, dharmalepas prastistha Siwa, dharma kasogatan, dan karesyan. Namun dari 4 jenis bangunan suci itu tidak jelas mana yang candi dan mana yang bukan candi. Menurut Soekmono (1993:70) yang mungkin dikatakan candi adalah jenis dharma haji yang kurang lebih berjumlah 27 buah, di antaranya: Kagenengan, Tumapel, Kidal, Jajaghu, Weda-wedwan, Tudan, Pikatan, Bukul, Jawa-Jawa, Antang, Antasari, Kalangbret, Jaga, Balitar, Cilabrit, Waleri, Babeg, Kukap, Lumbang, Pager, Antahpura, Segala, Simping, Ranggapura, Buddhi, Kuncir, Prajnaparamita Puri, dan Bhayalango. Salah satu kitab terkenal yang dibuat pada masa raja Hayam Wuruk adalah Negarakertagama. Negarakertagama adalah puja sastra yang diperuntukkan baginda raja di Wilwatikta (sebutan untuk Hayam Wuruk). Membahas kronologi atau tata cara pendirian candi, penulis mendasarkan pada Kitab Negarakertagama yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit. Negarakertagama dijadikan bahan utama untuk interpretasi data tata cara pendirian candi. Interpretasi ini dilakukan dengan triangulasi data yang didapat dari isi pupuh-pupuh Negarakertagama dan pada kondisi tertentu ditriangulasikan 5 pula dengan isi Serat Pararaton, Kitab Tantu Panggelaran, dan data arkeologis lainnya, tetapi kecenderungannya terfokus pada Negarakertagama. Negarakertagama yang digunakan adalah hasil saduran Slametmulyana (1979). Keabsahan saduran tentunya dapat dipercaya, walaupun sebenarnya lebih baik apabila penulis bisa memahami teks aslinya. Namun karena keterbatasan penulis dalam bidang ini, maka penulis merujuk pada naskah saduran tersebut. Negarakertagama sangat berharga bagi pengetahuan sejarah Majapahit. Beruntunglah kita yang bisa mendapatkan data sejarah melalui Negarakertagama. Menurut Damais (1995:97) di Indonesia tampak adanya ketidakpastian dalam pelestarian dokumen kuno. Karena Damais melihat bahwa Negarakertagama yang dibuat tahun 1365 M oleh Prapanca itu secara kebetulan ditemukan dan diselamatkan oleh Brandes pada tahun 1894 M. Naskah dalam bentuk lontar itu ditemukan di Lombok yang akan dijadikan kayu bakar dan sedang ditumpuk di gudang. Seakan Damais ingin membuka mata bangsa Indonesia akan "kurang perhatiannya" bangsa Indonesia terhadap peninggalan sejarah bangsanya. Perhatian yang kurang dari bangsa Indonesia terhadap data sejarah ini menyebabkan sulitnya sebuah rekonstruksi sejarah, termasuk tata cara pendirian candi. Naskah Negarakertagama tersebut ditemukan bertepatan dengan ekspedisi Belanda melawan Tjakranegara pada tahun 1894 M. Naskah yang diselamatkan Brandes tersebut adalah naskah yang disalin di Bali pada tahun 1740 M, kemudian diterbitkan dalam aksara Bali pada tahun 1902 M oleh Brandes. Menurut Slametmulyana (1979:11) Negarakertagama yang berbentuk kakawin itu menduduki urutan kedua setelah piagam-piagam/prasasti (misalnya piagam-piagam Singasari) dalam kaitannya dengan keabsahan/validitas sumber sejarah, sedangkan Pararaton menduduki urutan ketiga setelah Negarakertagama. Hal ini senada dengan ungkapan Soekmono (1981:120) yang menyatakan bahwa Pararaton dimaksudkan sebagai sumber sejarah sangat kurang dapat dipercaya, karena isinya bersifat dongeng. Sementara Negarakertagama menurut Soekmono (1981:118) dikatakan penting sekali untuk sejarah, karena yang diuraikan adalah riwayat Singasari dan Majapahit dari sumber-sumber pertama dan ternyata sesuai dengan prasasti-prasasti. Sedangkan kitab-kitab lain seperti Babad Tanah Jawi, Tantu Panggelaran, Serat Sastramiruda dan lain-lain, jika dipakai sebagai sumber sejarah keabsahannya di bawah ketiga sumber tersebut. Tata Cara Pendirian Candi Data tentang tata cara pendirian candi ini akan diuraikan secara urut berdasarkan beberapa data sejarah sebagaimana disebutkan sebelumnya, di antaranya: kitab Negarkertagama, Pararaton, Tantu Panggelaran, ditambah buku dari Soekmono (1981), Djoko (1983), Santiko (1987, 1992, 1995). Cara penguraiannya adalah menyebut tata caranya kemudian menunjuk data sejarahnya. Berdasarkan beberapa literatur sebagaimana tersebut sebelumnya, maka kronologi atau tata cara pendirian candi adalah: 6 1. Ada sebuah peristiwa yaitu raja atau kerabat raja meninggal dunia/wafat. Peristiwa ini diceritakan oleh Negarakertagama pada beberapa pupuh di antaranya: Pupuh XL: 5 yang menceritakan bahwa Sri Ranggah Rajasa / Sang Girinata / Ken Arok kembali ke Siwa-pada (meninggal) pada tahun Saka muka lautan Rudra (1149 S = 1227 M) dan dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa dan di Usana bagai Budha. Pupuh XLI: 1 adalah mangkatnya Anusapati pada tahun Saka perhiasan gunung Sambu (1170 S = 1248 M) dicandikan di Kidal. Peristiwa yang sangat menarik bagi Prapanca sebagai penggubah Negarakertagama adalah meninggalnya nenek dari Raja Hayam Wuruk. Peristiwa ini menarik bagi Prapanca karena Negarakertagama memang sebagai puja sastra kepada Raja Hayam Wuruk. Peristiwa itu terdapat pada pupuh II: 1, bahwa Sri Rajapatni / Gayatri / Prajna Paramita meninggal sebagai wikuni tua pada tahun Saka dresti saptaruna (1272 S = 1350 M). Peristiwa ini nantinya menjadi tumpuan pembahasan tata cara pendirian candi. Sebenarnya masih banyak peristiwa meninggalnya raja yang diungkap oleh Negarakerta-gama, namun tidak perlu diuraikan satu per satu. Sebagai bandingan data sejarah, tidak hanya Negarakertagama yang mencatat meninggalnya raja, Serat Pararaton pun mencatat pula. Catatan dalam Pararaton di antaranya pada akhir bab IV dijelaskan bahwa Apanji Toh Jaya wafat pada tahun Saka 1172 S (11250 M), pada bab IV dijelaskan bahwa Ranggawuni wafat pada tahun 1194 S (1272 M) dicandikan di Jajaghu, Kertarajasa wafat pada tahun 1257 S (1335 M) dicandikan di Antapura termuat pada bab VII, dan masih banyak lagi catatan meninggalnya raja. Perlu diketahui bahwa beberapa angka tahun meninggalnya raja pada catatan Negarakertagama dan Serat Pararaton sangat berbeda, karena validitas data yang lebih tinggi adalah Negarakertagama maka yang dipercaya sebagai data sejarah adalah yang ada pada Negarakertagama. Pada peristiwa meninggalnya raja atau kerabat dekat raja, tentunya terdapat peristiwa ritual saat itu, namun Negarakertagama dan Pararaton tidak mencatat rangkaian ritual yang terjadi. Hanya setelah 12 tahun setelah meninggalnya raja atau kerabat raja dicatat adanya peristiwa besar yang disebut Sradha. Berdasarkan sistem religi sebagaimana tertulis di atas maka konsep bertemunya Brahman dengan atman dapat dilacak sebagai konsep yang melatarbelakangi upacara ritual ini. Syarat dapat bertemunya atman (manusia/ mikrokosmos) dengan Brahman (Tuhan/makrokosmos) adalah kesucian atau bersihnya 2 unsur manusiawi (jiwa/rohani dan raga/jasmani) dari mala atau cela. Dari unsur jiwa/rohani lengkapnya jiwatman (atman perseorangan) dalam ajaran Upanisad akan terlahir kembali (reinkarnasi) masuk dalam lingkaran samsara apabila masih ada dosa, cela atau mala, maka dari itu manusia mencita-citakan moksa, lepas dari samsara, bebas dari hukum karma (Soekmono 1981:14-15). Jika manusia telah meninggal maka diadakan upacara ritual tertentu agar lepas dari samsara itu, contohnya ritual rutin secara bertahap atau beberapa hari tertentu setelah meninggalnya raja atau kerabat raja. Jika jiwa/rohani telah suci, maka raga/jasmani juga harus bersih. 7 Upacara pembersihan raga/jasmani ini tidak diberitakan oleh Negarakertagama maupun Pararaton. Di Bali yang masih meneruskan tradisi Hindu, terdapat upacara pembersihan raga/jasmani yang diselenggarakan secara turun-temurun yaitu upacara ngaben. Ngaben dilakukan dengan membakar jenasah agar jenasah tersebut secara ragawi/jasmaniah akan hilang/bersih. Setelah dibakar maka abu jenasah ini tidak disimpan di dalam peti kecil (peripih) sebagai abu persembahan kepada Brahman yang akan ditanam di dalam kuil/candi atau dasar kuil/candi, tetapi di Bali ternyata seluruh abu jenasah itu dibuang ke laut yang terkenal dengan nama upacara pelarungan abu jenasah. Dengan demikian gugurlah pendapat yang menyatakan bahwa candi adalah makam raja atau kerabatnya. Di Bali pernah terjadi pemakaman mayat di sebuah lokasi, tetapi hal ini ternyata bukanlah untuk selamanya, tetapi untuk sementara. Mayat yang dimakamkan hanya dimaksudkan untuk menunggu mayat lain supaya bisa disatukan pada saat diadakan upacara ngaben. Penyatuan ini dimaksudkan agar lebih irit biaya dalam penyelenggaraan ngaben, terutama bagi mayat yang keluarganya tidak mampu. Dengan demikian pemakaman itu hanya bersifat pragmatik tidak atas dasar sistem religi, karena bersifat sementara dan untuk tujuan penghematan dalam penyeleng-garaan ngaben yang dilakukan secara berkelompok. Selain itu konsep pemakaman ini sebenarnya ada pada sistem religi Islam, karena pada sistem religi Islam manusia tidak bersatu dengan Tu-han (Allah), tetapi cita-cita luhur pemeluk Islam adalah manusia/orang yang meninggal dapat dite-rima di sisi Allah. Konsep “bersatu” berbeda dengan konsep “diterima di sisi”, “bersatu” berarti le-bur jadi satu, sedangkan “diterima di sisi” berarti ada jarak dengan Yang Maha Kuasa (makrokos-mos). Pada sistem religi Islam juga terdapat konsep bahwa manusia terbuat dari tanah maka akan kembali ke tanah, hal ini akan memunculkan konsep pemakaman di dalam tanah tersebut. Pada peristiwa meninggalnya raja atau kerabatnya dimungkinkan diikuti dengan peringatan rutin atas wafatnya raja atau kerabat raja tersebut, misalnya 3 hari, sepasar, 7 hari dan seterusnya sampai 12 tahun setelah meninggal (Sradha). Peringatan rutin atas meninggalnya raja atau kerabat raja ini tidak termuat dalam Negarakertagama atau Pararaton, tetapi rangkaian upacara Sradha uraian Negarakertagama ini hampir sama dengan rangkaian upacara mumukur atau ngemadya yang masih dilestarikan di Bali (Soedarso 1973:13-15). 2. Membuka tanah dan memilih lahan yang tepat/persiapan tanah. Kegiatan ini mungkin sudah termasuk rangkaian awal upacara Sradha, karena Negarakertagama tidak menyebutkan hal ini. Usaha membuka tanah untuk dharma agama dapat dilihat pada pupuh LXXXII: 2 Negarakertagama. Dalam ajaran Hindu di masa Majapahit terdapat 6 dharma agama (Negarakertagama pupuh LXXXII: 1/3), salah satunya adalah memelihara dan membuat bangunan suci termasuk candi di dalamnya. Pupuh LXXXII: 2 menjelaskan bahwa Sri Nata Singasari membuka ladang 8 luas di daerah Sagala. Pada pupuh tersebut juga dijelaskan bahwa Sri Nata Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, Pajang, kemudian mendirikan perdikan Budha di Rawi, Locanapura, dan Kapulungan. Baginda Hayam Wuruk membuka ladang Watsari di Tigawangi. Berdasarkan beberapa perbandingan kitab Vastusastra diketahui bahwa tanah untuk candi dipilih jenis tanah yang baik berdasarkan warna, bau, kelandaian, jenis tanaman, kandungan tanah dan ada pengujian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah ini (Santiko 1995: 8). Syarat lain tanah harus subur terindikasi dengan banyaknya kandungan air dari dalam tanah. Pengujian kandungan air ini salah satunya adalah dengan meletakkan selembar daun kering di sore hari di atas permukaan tanah. Apabila permukaan daun yang menghadap ke tanah di pagi harinya dipenuhi dengan embun/titik-titik air, maka tanah tersebut dianggap banyak kandungan air/subur. Selain itu agar subur, tanah tersebut harus dibajak seperti layaknya pengolahan tanah untuk sawah (Santiko 1995:8). Tanah untuk candi harus subur, hal ini terkait dengan konsep kesuburan yang ada pada sistem religi Hindu (lihat uraian selanjutnya). Selain subur syarat kedua, ketentuan lokasi candi di dalam kitab selain Manasara adalah pendirian bangunan suci sebaiknya dekat dengan air (tirtha) baik air sungai, terutama di dekat pertemuan dua sungai, danau, laut dan bahkan bila tidak ada harus dibuatkan kolam buatan halaman kuil, atau diletakkan sebuah jambangan berisi air di dekat pintu masuk bangunan suci tersebut (Santiko 1995:8). Hal ini sesuai dengan kosmolgi penciptaan candi dalam kitab Tantu Panggelaran bahwa gapura candi sebelah barat dijaga oleh dua raksasa bernama Kala dan Anungkala, gapura tersebut terletak di Pengavan (Santiko 1992:48). Pengavan atau bengawan adalah tempat luas berisi air seperti danau. Kedudukan 2 raksasa (dwarapala) Kala dan Anungkala di bengawan ini bisa dijumpai pada beberapa peninggalan candi yang masih ada hingga sekarang, misalnya di kompleks candi Panataran (Palah) Blitar Jawa Timur. Pada candi Panataran ini kedudukan dwarapala berada di lekukan tanah di bawah rata-rata tanah di sekitarnya. Walaupun lekukan tanah tersebut kering, tampaknya dahulu tanah cekung tersebut berfungsi sebagai bengawan. Hal serupa tampak pula pada kedudukan dwarapala pada arca Totok Kerot di Kunir Kediri Jawa Timur dan dwarapala besar dekat candi Singasari Malang. Syarat ketiga, lokasi bangunan suci (candi) didirikan di puncak bukit, lereng bukit, lembah atau hutan. Menurut Tantra Samuccaya disebutkan bahwa bangunan suci di dirikan di puncak bukit, di lereng gunung, di hutan, di lembah dan sebagainya (Kramrisch 1946 I:3-7 dalam Santiko 1995:8). Syarat semacam ini sesuai dengan kosmologi Hindu bahwa candi adalah replika meru atau tiruan gunung. Hal ini sesuai dengan panteon candi yang termuat dalam kitab Tantu Panggelaran. Pada kitab Tantu Panggelaran dijelaskan bahwa candi sebagai replika meru merupakan gambaran tentang Mahameru sebagai tempat kediaman bhatara Guru atau Siwa, dalam kitab ibi diidentikkan dengan gunung Semeru di Jawa (Santiko 1992:48). Selanjutnya dalam kitab Tantu Panggelaran dinyatakan 9 bahwa bhatara Guru menjalankan yoga di arggha (puncak) Sang Hyang Mahameru, pandangannya tertuju ke ujung hidung, dan ia menghadap ke arah barat (Pigeaud dalam Santiko 1992:48). 3. Tindakan selanjutnya menurut beberapa Vastusastra (termasuk Manasara) adalah mencari titik pusat halaman dengan menggunakan sebatang sangkhu yaitu sebatang kayu yang dibuat khusus. Setelah itu dicari keempat mata angin serta arah keempat penjuru lainnya (Santiko 1995:9). Keempat arah mata angin ini terkait dengan kedudukan Brahman sebagai purusa dan membentuk diagram (lihat gambar 1). 4. Kemudian menggambar diagram tersebut di atas tanah. Diagram yang terkenal adalah Vastupu-rusamandala dan sebenarnya masih ada jenis diagram lainnya (Santiko 1995:9). Diagram Vastu-purusamandala berbentuk bujursangkar dan dibagi menjadi kotak-kotak kecil. Jumlah kotak-kotak kecil berbeda-beda tergantung jenis bangunan suci yang akan didirikan. Jumlah kotak mulai dari 1 s/d 1024 dan yang dipakai untuk bangunan suci adalah kotak 49 (Sthandila) dan 64 (Manduka, Chandika) terkadang kotak 81 (Paramasayika) (Santiko 1995:9). Penggambaran diagram ini tampaknya sering digunakan untuk pembangunan kuil Budha dan juga untuk stupa Budha. Sebagaimana diketahui bahwa pada agama Budha istilah candi sebenarnya adalah stupa misalnya stupa Borobudur. Pada stupa Borobudur juga menerapkan diagram dengan dasar kotak 9. Diagram ini disebut Vastupurusamandala/Wastupurusamandala yang berarti mandala vastu (bangunan, tempat) purusa. Purusa yaitu asura tanpa nama, tidak lain adalah Brahman sendiri, turun “mengorbankan“ diri, tubuhnya menyatu dengan tanah dan menjadi pelindung (Vastupa) tempat dan bangunan yang akan didirikan di atasnya (Santiko 1995:9). Oleh dewa-dewa purusa tersebut ditelungkupkan di atas tanah (vastu) dengan pusar tepat di titik pusat diagram, kepala menghadap ke arah timur bagi diagram berkotak 64 dan ke arah timur laut bagi diagram berkotak 81, kepala menempel di bahu kiri, kedua kaki dan tangan terbentang menggapai keempat sudut mata angin (Acharya 1993, IV:53; Kramrisch 1946, I:73-79; Rao 1988:22-23, dalam Santiko 1995: 9-10). Penggambaran purusa dapat dilihat sebagai berikut (lihat gambar 1). 10 Gambar 1: Kedudukan purusa sebagai titik pusat diagram pada candi. Di sinilah tempat Purusa (Brahman), menjadi tenaga cipta sekaligus pelindung bangunan suci dan kekuatannya terkumpul di titik pusat yang disebut brahmasthana (Santiko 1995:10). Oleh karena itu brahmasthana ini menjadi penting dan dianggap sakral, terbukti pada masa Majapahit dijadikan nama pohon yang ditanam berjajar di kota raja (Negarakertagama pupuh VIII:3). Brahmasthana dikelilingi oleh 2 kelompok dewa penjaga. Kelompok pertama berkeliling dekat brahmasthana, berjumlah 12 dewa-dewa perbintangan (Naksatra) dan kelompok kedua berkeliling di dekat batas diagram adalah kelompok Padadevata yang berjumlah 32 terrmasuk di dalamnya dewa-dewa penjaga 8 arah mata angin (Astadikpalaka), dan 4 Lokapala (Kramrisch 1946:89-97, dalam Santiko 1995:10). Selanjutnya apakah diagram Vastupurusamandala ini dipakai untuk candi di Jawa? Menurut Santiko (1995:11) untuk menentukannya dapat diperhatikan pertimbangan sebagai berikut: a. Walaupun diagram Vastupurusamandala tidak dimaksudkan untuk menentukan denah halaman maupun denah kuil, tetapi akhirnya hal itu tidak bisa dihindarkan (selengkapnya lihat Santiko 1995:10). b. Garbhaghra atau ruang tengah kuil utama/induk (prasada) harus tepat di titik brahmasthana. 5. Penyucian tanah. Pemberkahan tanah/penyucian tanah tidak dijelaskan di dalam Negarakertagama apakah sebagai rangkaian upacara Sradha atau tidak. Dimungkinkan penyucian tanah ini tidak termasuk rangkaian upacara Sradha, karena sebagai contoh adalah Sradha Sri Rajapatni yang diadakan oleh Hayam Wuruk pada tahun Saka bersirah empat (1284 S = 1362 M) (Negarakertagama pupuh LXII: 2). Sri Rajapatni dicandikan di Kamal Pandak. Ternyata pada kitab Negarakertagama pupuh LXVII: 3 disebutkan bahwa tanah di Kamal Pandak yang dijadikan lokasi candi untuk neneknda Hayam Wuruk (Sri Rajapatni) telah disucikan oleh Jnyanawidi (nama pendeta) pada tahun Saka 1274 (1352 M) 11 (Slametmulyana 1979:308). Dengan demikian penyucian tanah Kamal Pandak telah dilakukan 10 tahun sebelum upacara Sradha (Sradha Agung) tersebut, berarti 2 tahun setelah meninggalnya Sri Rajapatni. Dimungkinkan 2 tahun setelah meninggalnya nenek Hayam Wuruk ini masuk sebagai rangkaian upacara rutin memperingati meninggalnya raja atau kerabat raja, dengan demikian tidak masuk dalam rangkaian upacara Sradha. Tujuan pendirian candi di Kamal Pandak ini adalah untuk mempersatukan Jawa kembali (Negarakertagama pupuh LXVIII:2 baris 2 dan baris 4). Siapa yang dimaksud Jnynawidi itu, dapat dilacak pada Negarakertagama pupuh LXIX: 1, yaitu seorang pendeta yang telah lanjut usia, faham akan tantra, penghimpun ilmu, laksana titisan Empu Barada (Slametmulyana 1979: 308). Empu Bharada adalah seorang pendeta dari Lemah Citra yang secara mitologis membelah tanah Jawa menjadi 2 yaitu Jenggala (Singasari) dan Panjalu (Kediri) dengan mengucurkan air kendinya. Pada saat pembelahan ini jubah sang pendeta tersangkut sebuah pohon asam (kamal). Maka dikutuklah pohon asam tersebut agar selamanya pendek (pandak), maka lahirlah nama tempat tersebut sebagai Kamal Pandak (Negarakertagama pupuh LXVIII:1-5). Kamal Pandak inilah sebagai batas negara Jenggala dan Panjalu pada masa pemerintahan Airlangga. Dimungkinkan nama Kamal Pandak tersebut sekarang menjadi Pandakan di Jawa Timur. Penyucian tanah ini disertai pula dengan upacara doa kepada Brahma/pemberkahan (Negarakertagama pupuh LXVII: 3/4 dan pupuh LXIX: 2/2). Sebagaimana diketahui Brahma adalah dewa pencipta. Selain dicandikan di Kamal Pandak, Rajapatni juga dicandikan di Bayalangu (Negarakertagama pupuh LXIX: 2 baris 1). Penyucian tempat untuk Rajapatni ini juga dilakukan oleh pendeta Jnynawidi sebagaimana penyucian tanah di Kamal Pandak (Negarakertagama pupuh LXIX: 2 baris 2). Contoh lain upacara penyucian tanah ini adalah pada upacara pembangunan candi di Bukit Sulang, Lemah Lampung dan Anyawasuda oleh Sri Baginda Jiwana (Negarakertagama pupuh LXXX:2/1) dan tanahnya diberkahi oleh upasaka wreda mantri (Negarakertagama pupuh LXXX: 2/4). 6. Setelah penentuan diagram candi/bangunan suci, menurut Negarakertagama terdapat serangkaian upacara Sradha (upacara 12 tahun setelah meninggalnya raja atau kerabat raja). Berdasarkan pendapat Djoko (1983) bahwa peripih disimpan dalam perigi, maka perigi disiapkan dulu sebelum Sradha. Ditafsirkan waktunya pada tahun yang sama dengan acara Sradha namun dalam hari atau bulan yang berbeda. Berdasarkan uraian Soekmono (1977, 1981), peripih ditanam pada dasar bangunan, maka ditafsirkan perigi tidak perlu dibuat sebelum Sradha. Perigi bisa dibuat serangkaian pada upacara Sradha, guna meletakkan arca bunga di atasnya. Uraian Soekmono ini juga cenderung pada tahun yang sama, tetapi berlainan hari atau bulan saat Sradha berlangsung. Rangkaian upacara Sradha berdasarkan Negarakertagama pupuh LXIII s/d LXVII adalah: 12 a. Pelukis dan orang-orang yang ditugasi, menghias lingkungan dan peralatan Keraton yang akan dipakai upacara Sradha. b. Diadakan upacara pembacaan mantra, mudra, japa, doa, dan mengheningkan cipta dipimpin oleh pendeta Stapaka. c. Upacara pengeluaran arca bunga sebagai arca perwujudan yang sengaja dibuat sebelum upacara Sradha, diiringi dengan tetabuhan. Arca tersebut didudukkan pada singgasana. d. Persembahan acara oleh para raja negara bawahan, pembesar, ksatria, pendeta dan lain-lain, disertai dengan sajian makanan, pertunjukan dan derma kepada orang miskin. e. Arca bunga diturunkan kembali, dengan upacara dan pembagian makanan. f. Peletakan pripih pada perigi, atau diletakkan di dasar candi, sedangkan kaki candi sudah mulai dibangun sejak ini. g. Penempatan arca bunga di atas perigi. Penempatan ini tentunya diberi alas yoni dibawahnya. Arca bunga sebagai arca perwujudan merupakan lambang dewa yang menjadi penitis raja tersebut. Dengan kata lain dewa yang disimbolkan sekaligus sebagai legitimasi kekuasaan raja. Jika arca perwujudan telah dibuat maka bilik candi dibangun setelahnya, disusul pembangunan atap dan mahkota candi. Selanjutnya pembuatan relief candi mulai dikerjakan oleh stapaka. 7. Setelah candi selesai dibuat hingga mahkota, maka diadakan upacara peresmian atau abhiseka. Pada upacara abhiseka atau peresmian candi biasanya dilakukan dengan penyucian arca perwujudan (bisa juga dalam bentuk lingga) sebagai simbol laki-laki, dibasuh dengan air amerta. Air amerta yang membasahi arca perwujudan akan masuk ke dalam yoni sebagai simbol kewanitaan, lalu masuk ke bagian cerat yoni. Dari bagian cerat yoni ini air amerta akan masuk ke dalam perigi, lalu akan membasahi peripih candi dan selanjutnya air akan masuk ke purusa bertemu dengan Brahman dan juga air akan kembali ke tanah bertemu dengan Brahma (dewa pencipta) yang telah dipuja saat penyucian tanah candi tersebut. Demikianlah mengapa air sangat penting bagi pendirian candi, karena digunakan sebagai sarana penyucian pada upacara ritual. Demikian pula pada sistem religi Islam air di masjid atau mushola sangat memegang peranan penting untuk penyucian yaitu berwudlu. Gambaran umum struktur candi dalam kaitannya dengan upacara abhiseka dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut ini: 13 Gambar 2: lapik teratai merah dan peti Nawasanga penyimpan peripih dari Candi Jalatunda yang akan diletakkan di perigi atau ditanam di dasar candi, berisi unsur-unsur persembahan kepada Dewa (abu dan tulang binatang, lempengan logam, dll.) (sumber: Soekmono, 1981: 18). Gambar 3: Struktur candi tampak samping dengan bilik candi, arca perwujudan, yoni, perigi, dan peripih tampak samping (diadaptasi dari: Djoko, 1983). 8. Usaha menyempurnakan candi. Usaha penyempurnaan candi ini jelas ada karena terbukti pada beberapa kompleks candi ditemukan beberapa candi yang berbeda angka tahunnya, misalnya di kompleks Panataran dan Sukuh. Di kompleks candi Panataran ditemukan ada beberapa angka tahun di antaranya: 1119 S (1197 M), 1241 S (1319 M), 1242 S (1320 M), 1245 S (1323 M), 1269 S (1347 M), 1291 S (1360 M), 1295 S (1373 M), 1297 S (1375 M), 1301 S (1379 M), 1337 S (1415 M), dan 1376 S (1454 M) (Soekmono 1993:72). Perbedaan angka tahun ini menunjukkan bahwa pada sebuah kompleks candi tidak dibangun satu masa raja yang berkuasa sekaligus, tetapi ada usaha penyempurnaan, renovasi, dan penambahan. Penyempurnaan, renovasi, dan penambahan candi ini bahkan terpaut ratusan tahun atau pada pemerintahan raja yang berbeda. Bukti lain bahwa candi itu tidak dibuat langsung jadi adalah adanya beberapa relief yang belum selesai dibuat (yang bisa diamati 14 sekarang), misalnya relief tokoh Panji yang terdapat pada pilar candi Tigawangi, tampak masih dipahat secara global, belum selesai dibuat detailnya. Contoh lain adalah adanya beberapa relief yang panelnya kosong, ada juga pahatan yang belum selesai misalnya di Candi Surawana. Bukti lain bahwa candi dibangun secara berkelanjutan adalah Negarakertagama pupuh LXVII: 3 baris 2 bertuliskan sebagai berikut: "Karya yang masih menunggu, menyempurnakan candi di Kamal Pandak". Berdasarkan kalimat ini ditafsirkan bahwa candi di Kamal Pandak sudah ada tetapi belum sempurna, dan menunggu karya dari para penerus generasi saat itu untuk menyempurnakan, termasuk uluran tangan (kerja) Hayam Wuruk. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa sebelum upacara Sradha itu candi telah dipersiapkan walaupun masih batu pertama atau pondasi, tetapi yang jelas sudah dilaksanakan acara pembersihan areal candi (disucikan) sebagaimana diuraikan sebelumnya. Selain itu bukti bahwa candi dibangun secara berkelanjutan adalah pembangunan candi untuk Sri Rajapatni di tempat kedua (Bayalangu), yaitu bunyi pupuh Negarakertagama yang menjelaskan bahwa jika candi Bayalangu telah selesai/sempurna diberi nama Wisesapura (Negarakertagama pupuh LXIX: 2 baris 4). Dari uraian di atas sebenarnya Negarakertagama mengisyaratkan bahwa selain dicandikan di Kamal Pandak, Rajapatni juga dicandikan di Bayalangu (Negarakertagama pupuh LXIX:2 baris 1). Hal ini menunjukkan bahwa: (1) seorang raja atau kerabat raja bisa dicandikan di dua tempat, (2) Kamal Pandak (tempat pertama) berhubungan dengan upacara Sradha, di Bayalangu (tempat kedua) tidak berhubungan dengan upacara Sradha. Bukti lain bahwa candi tidak dibuat pada satu pemerintahan raja dan terus disempurnakan juga diuraikan pada Negarakertagama pupuh LXI: 4 dan pupuh LXII: 1, bahwa Hayam Wuruk juga berusaha merenovasi candi Simping di Blitar Jawa Timur pada tahun Saka dengan candra sengkala tiga badan dan bulan (1283 S = 1361 M). Bunyi pupuh LXI: 4 Negarakertagama adalah: “Meninggalkan Lodaya menuju desa Simping Ingin memperbaiki candi (dharma haji) Menaranya rusak, dilihat miring ke barat Perlu ditegakkan kembali ke arah timur” Sedangkan bunyi pupuh LXII: 1 Negarakertagama (kelanjutan pupuh LXI: 4) adalah: “Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prasasti, yang dibaca lagi Diukur panjang lebarnya; di sebelah timur sudah ada tugu Asrama Gunung-gunung diambil sebagai denah candi (dharma haji) Untuk gantinya diberikan Ginting, Wisnurare di Bajradara” Dari pupuh ini tersirat bahwa perbaikan atau renovasi candi ini juga menggunakan asrama Gunung-gunung sebagai denah candi atau diagram candi sebagaimana dijelaskan sebelumnya adanya penerapan diagram Vastupurusamandala. Dengan demikian pembangunan candi selanjutnya diserahkan kepada generasi berikutnya namun tetap berdasarkan kitab yang relevan yang satu 15 kosmologi dengan masa sebelumnya atau berdasarkan master plan yang sama. Hal ini sangatlah berbeda dengan pembangunan kota saat ini. Seakan antar mazab pemerintahan bersaing mendirikan bangunan yang ingin dikenal dan dikenang oleh generasi kemudian. Ego dan individualistik tiap mazab pemerintahan saat ini sangat kelihatan, berbeda dengan bangunan klasik Hindu-Budha yang membuat bangunan suci untuk bersama oleh bersama dengan tidak meninggalkan ciri khas master plan sebelumnya. Pada masa klasik ini generasi berikutnya berusaha menyelaraskan dan menyerasikan dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya, berbeda dengan pembangunan di jaman modern ini. Sebagai contoh kurang tepatnya penerapan master plan pada saat ini adalah pembangunan Gedung Pandanaran yang sekarang milik Pemkot Semarang (dulunya gedung BDNI) sebagai ciri gedung mega politan bersaing dengan karakter gedung kolonial Lawang Sewu, seakan berebut popularitas. Banggakah Pemkot Semarang? Penutup Berdasarkan latar belakang pendirian candi dan penelitian laboraturium atas kandungan zat organik pada abu jenasah di dalam peripih candi, akhirnya diketahui bahwa candi bukanlah makam raja atau kerabat raja. Berdasarkan kajian historis (arkeologis) ternyata candi adalah salah satu bentuk perwujudan dharma agama (dalam hal ini adalah dharma haji) bagi raja dalam konteks sistem religi Hindu sekaligus sebagai monumen peringatan meninggalnya raja atau kerabatnya. Dengan demikian perlu diluruskan pandangan di kalangan para pendidik dan peserta didik yang selama ini tertanam konsep bahwa candi adalah makam raja. Tata cara pendirian candi menunjukkan bahwa pendirian candi benar-benar didasarkan atas sistem religi yang berlaku saat itu, yaitu hubungan kosmologis antara makrokosmos dan mikrokosmos. Pada hubungan ini terungkap bahwa Brahman mengorbankan diri sebagai purusa (pusat candi) menyatu dengan tanah, merupakan tenaga gaib bagi candi yang akan dibangun di atasnya. Dewa Siwa berperanan pada penentuan panteon dan arah mata angin candi. Candi sebagai replika Mahameru, di puncak Mahameru Siwa beryoga pandangannya tertuju ke ujung hidung, dan ia menghadap ke barat. Hal ini menyebabkan pintu candi menghadap ke barat. Pada saat pembangunan candi dianggap selesai, hal ini masih perlu penyempurnaan dan pemeliharaan di kemudian hari. Peran Wisnu sebagai pemelihara akan memberikan pula tenaga gaib pada proses pemeliharaan ini. Dengan demikian ada satu kesatuan pemberkatan kerja dalam proses penciptaan candi. Akhirnya bersatunya atman (mikrokosmos) dengan Brahman (makrokosmos) merupakan sistem religi Hindu yang mendasari berdirinya sebuah candi, karena sistem ini akan melahirkan konsekuensi kesucian jasmaniah (raga) dan rohaniah (jiwa) para pemeluknya. Hanya atman yang suci jasmaniah dan rohaniah yang dapat bersatu dengan Brahman. Dalam kaitannya dengan kesucian jasmaniah dan 16 rohaniah maka muncul ngaben dan upacara pelarungan. Pelarungan sebagai sarana penyucian zatzat jasmaniah, sedangkan untuk penyucian rohaniah muncul istilah moksa, ruwatan dan reinkarnasi. Pembangunan candi yang dilakukan raja sesudahnya pada masa Hindu Budha, sangat konsisten dengan master plan yang telah dibuat raja sebelumnya. Hal ini jauh berbeda dengan pembangunan gedung pada masa sekarang. Meskipun dapat dilacak tata cara pendirian candi, tetapi yang masih gelap adalah siapa pembuat candi di Indonesia sebagaimana diungkapkan Bosch di bagian pendahuluan. Dari kekelabuan data historis ini, ada satu hal yang dapat disepakati bahwa pembangunan candi di Indonesia pada hakekatnya didasarkan atas dharma agama, dharma agama ini memerintahkan untuk membuat bangunan suci (candi) secara bersama-sama/gotong royong untuk kepentingan bersama bukan karya individual seperti karya seni Barat. Berdasarkan kebersamaan ini wajar bila pelaksana lapangan pembangunan candi tidak pernah terungkap data historisnya atau anonim sedangkan karya seni Barat sepertinya tidak syah apabila tidak ada tanda tangan pembuatnya (misalnya lukisan). Hal ini menunjukkan bahwa karya seni tradisi/klasik lebih bersifat untuk kebersamaan sedangkan Barat cenderung menonjolkan ego dan individualistik. Daftar Pustaka Damais, L. C.. 1995. Epigrafi dan Sejarah Nusantara. Jakarta: Efeo. Djoko, 1983. Trowulan Bekas Ibukota Majapahit. Jakarta: Balai Pustaka. Miksic, J. N. dan Endang Sri Hardiati S.. 1995. Sraddha Sri Rajapatni: An Exploratioan Of Majapahit Mortuary Ritual. Singapura: National Heritage Board. Moeliono, A. M. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Padmapuspita, J. 1966. Pararaton: Teks Bahasa Kawi dan Terjemahan Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Taman Siswa. Purwanto. 2005. “Kosmologi Gunungan Jawa.” Jurnal Seni Imajinasi, Volume 2 Januari 2005. Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Santiko, H.. 1987. “Hubungan Seni dan Religi: Khususnya dalam Agama Hindu di India dan Jawa.” Bunga Rampai Hasil Diskusi Ilmiah Arkeologi II: Estetika dalam Arkeologi Indonesia. Yogyakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Santiko, H.. 1992. Bhatari Durga. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Santiko, H.. 1995, Seni Bangunan Sakral Masa Hindu - Budha di Indonesia (Abad VIII – XV Masehi): Analisis Arsitektur dan Makna Simbolik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Tetap). Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 17 Slametmulyana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. Soekmono. 1977. Candi: Fungsi dan Pengertiannya. Jakarta: DP3M Dirjen Dikti Departemen P dan K. Soekmono. 1981. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius. Soekmono. 1993. “Peninggalan-Peninggalan Purbakala Masa Majapahit.” Bunga Rampai 700 Tahun Majapahit: Suatu Bunga Rampai. Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Soedarso SP. 1973. Proses Pembentukan: Pertemuan antara Kebudayaan Asli dengan Kebudayaan India. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI Yogyakarta. Subagya, R.. 1981. Agama Asli Indonesia. Jakarta Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka. Suru, I M.. 1983. Lintasan Sejarah Seni Rupa Timur Purba. Malang: IKIP Malang. Yudoseputro, W.. 1993. Pengantar Wawasan Seni Budaya. Tanpa Kota: Departemen P dan K. 18