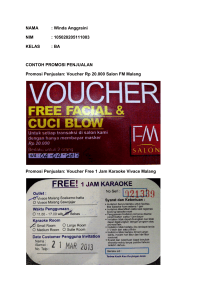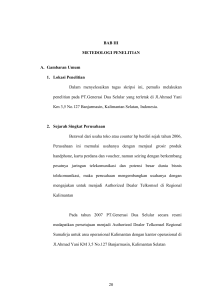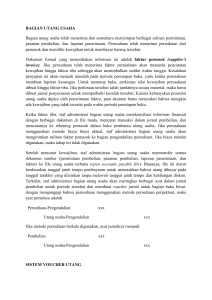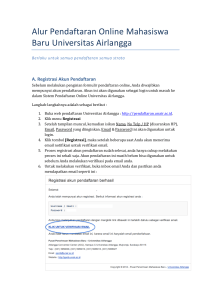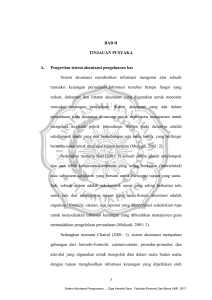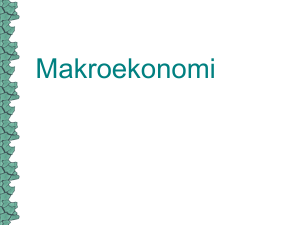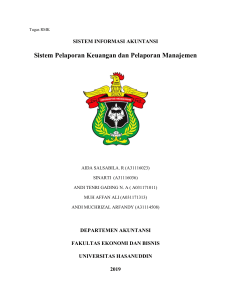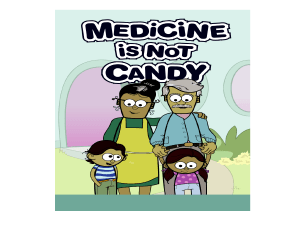School Choice: Cara Kebebasan Merespon
advertisement

School Choice: Cara Kebebasan Merespon Pendidikan Anggita Ludmila Pendidikan, adalah salah satu bidang yang paling krusial bagi sebuah negara, utamanya dalam membangun kapasitas bangsa.Setiap negara bekerja keras untuk menemukan sistem terbaik yang dapat menjamin kualitas dan kesetaraan pendidikan bagi masyarakatnya. Ketika seorang warga negara berpendidikan baik, ia akan mempunyai ilmu yang kelak dapat ia gunakan untuk membantu masyarakat dimana ia tinggal, maupun berkarya bagi negaranya. Hubungan antara kualitas pendidikan seseorang dengan masyarakatnya menciptakan ‘neighborhood effect’. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang mendorong masyarakat mengenyam pendidikan: program wajib belajar, berbagai macam beasiswa, sistem yang menitikberatkan pada sertifikasi pendidikan di berbagai aspek kehidupan, dan lain sebagainya untuk memastikan masyarakat tersebut terbangun dengan kualitas yang baik. Namun, seringkali ‘pergi sekolah’ tidaklah cukup. Selain memastikan sebanyak-banyaknya warga negara mendapatkan pendidikan, untuk menciptakan seorang berkualitas, tentunya pendidikan yang didapatkan tidak bisa dibuat dengan kualitas rendah. Pemerintah telah menetapkan standar pendidikan layak di seluruh sekolah, walaupun terjadi ketimpangan yang besar antara satu sekolah dengan sekolah lainnya: seringnya kita bertemu dengan orang cerdas dan sukses yang berasal dari serentetan sekolah bagus tertentu bisa menjadi gambaran bagaimana ketimpangan itu terjadi. Permasalahannya adalah jumlah sekolah ‘bagus’ lebih sedikit daripada yang tidak. Jika ini dibiarkan, berarti semakin sedikit orang-orang cerdas yang bisa membangun bangsa tadi. Lantas bagaimana? Hal ini kemudian menjadi salah satu pemikiran Milton Friedman – ia adalah Bapak dari konsep school choice, sebuah perspektif yang beranggapan bahwa setiap orang seharusnya dapat mengenyam pendidikan terbaik yang sesuai dengannya. Friedman mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat, dimana setiap anak sudah diplot ke sekolah-sekolah milik pemerintah yang berada di wilayah tempat ia tinggal – gratis. Dampak buruk dari kebijakan semacam itu biasanya terdapat pada kualitas dari sekolah yang tersedia: tidak semua sekolah yang disediakan oleh pemerintah berkualitas sangat baik – tentunya ini terjadi karena sistem penempatan otomatis membuat mereka akan selalu punya murid setiap tahun ajaran baru – dan ini membatasi kebebasan seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik baginya. Untuk menciptakan kebebasan yang lebih leluasa dalam memilih sekolah, Friedman menggagas sistem school voucher, yakni sebuah sistem yang memungkinkan orangtua untuk mengajukan sekolah tertentu yang dianggapnya terbaik untuk anaknya kepada pemerintah, untuk kemudian diberikan semacam voucher yang digunakan untuk membayar segala keperluan pendidikan anak tersebut di sekolah itu. Harapannya, setiap orang tidak harus terpaksa masuk ke sekolah tertentu yang berkualitas kurang baik, tetapi bisa memilih yang terbaik, sehingga mereka akan menjadi dampak yang baik pula bagi masyarakatnya di kemudian hari. Tentunya, sistem ini bukan tanpa perdebatan. Khususnya di Amerika Serikat, seringkali akhirnya orangtua mengajukan sekolah-sekolah swasta dengan kualitas baik untuk menjadi tempat anaknya menempuh pendidikan. Disinilah letak perdebatannya: pertama, uang pemerintah yang tadinya digunakan untuk membiayai sekolah negeri, harus terserap beberapa bagian ke sekolah swasta karena orangtua banyak memilihnya. Hal ini menjadi masalah, karena pada hakikatnya, sekolah negeri di AS menerima semua anak tanpa pandang identitas, berbeda dengan sekolah swasta yang seringkali berkaitan dengan suatu identitas tertentu. Seringkali yang terjadi, mereka dengan identitas ‘berbeda’ tidak diterima di sekolah swasta, yang akhirnya – menurut mereka – membuat sekolah negeri ‘mendapat input pelajar tidak sebaik sekolah swasta’ – dan oleh karenanya tidak dapat mengejar kualitas sekolah-sekolah swasta. Kedua, kembali lagi kepada identitas sekolah swasta yang seringkali berdasar pada agama, pembiayaan pemerintah bagi anak yang bersekolah di sekolah swasta seringkali dipandang sebagai penyatuan pemerintahan dan agama – yang ditentang oleh banyak masyarakat AS. Namun, terlepas dari itu (dan terlepas dari fakta bahwa sistem voucher memberikan kebebasan lebih bagi seseorang untuk memilih pendidikan), ada hal menarik terkait dengan sistem ini. Ekonom Caroline Hoxby dalam tulisannya The Economics of School Choice mengaitkan situasi kebebasan memilih ini dengan pasar bebas. Ibarat konsumen dalam berbelanja di pasar, orangtua atau peserta didik tentunya akan memilih produk terbaik – dalam hal ini sekolah – untuknya. Dengan pola pikir seperti itu, maka yang terjadi adalah sekolah akan berusaha meningkatkan kualitasnya untuk bersaing dengan sekolah lain, sehingga mereka menjadi sekolah yang dipilih oleh orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Semakin banyak orang memilih sekolah itu, tentunya semakin banyak uang yang akan masuk ke sana. Karenanya, sistem voucher, menurut Hoxby, justru dapat menjadi stimulan bagi banyak sekolah untuk menjadi yang terbaik ketimbang membuat mereka kalah bersaing seperti yang dikatakan argumen kontra sebelumnya. Dan ini dapat terjadi secara alamiah, tanpa pemerintah harus mengucurkan lebih banyak uang untuk secara khusus meningkatkan kualitas sekolah tertentu. Bukan berarti kemudian kita dapat leluasa mengatakan, ‘Mari! Terapkan sitem itu disini!’, namun, tentunya menarik untuk melihat bagaimana sebuah perubahan baik dapat dicapai tidak selalu dengan menunjuk-nunjuk pemerintah – malah, disarankan agar pemerintah tidak campur tangan terlalu banyak! Seperti yang dikatakan para penganut liberal pada umumnya, pemerintah tentu mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan, namun, pada tahap sangat dasar, yakni memastikan terciptanya sebuah standar dan situasi yang memungkinkan kompetisi yang adil. Meskipun untuk Indonesia pola pikir semacam itu masih cukup asing mengingat pemerintah mempunyai campur tangan besar di berbagai bidang, saya rasa tidak ada salahnya untuk menjadi lebih mandiri disini. Bayangkan jika semua serba ditangani pemerintah. Sudah bukan rahasia pemerintah Indonesia adalah korup. Sudah bukan rahasia bahwa pemerintahan Indonesia adalah birokrasi tanpa hasil. Jika anda meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas begitu banyak sekolah di negeri ini, saya yakin mereka akan menerimanya dengan senang hati: kesempatan membuat anggaran palsu! Setelah anggaran sudah jadi, implementasinya akan butuh waktu sangat lama, atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun jika kita mengacu pada sistem ‘school choice’ di atas, tentunya saya tidak dapat menjamin korupsi akan hilang sama sekali, kita bisa berharap sekolah akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, secara alamiah. Seperti Unilever, P&G, dan banyak produk konsumen lainnya. Tentu, kita bisa bilang, mungkin saja yang mendapat voucher justru mereka yang sudah mampu (terjadi juga di AS), atau bisa saja sekolah tertentu menyuap pemerintah supaya anak yang mengajukan voucher diarahkan ke sekolah mereka, dan cara-cara gelap lainnya. Namun, ketika kita mencari peningkatan kualitas layaknya pasar bebas, ini merupakan cara yang baik. Pemerintah cukup menetapkan standar tertentu terhadap kurikulum, dan sekolah dapat berkompetisi menjadi yang terbaik. Buat sistem alokasi pendanaan menjadi per-orangan ketimbang jumlah pasti untuk satu sekolah, sehingga sekolah akan berusaha untuk mendapatkan murid sebanyak-banyaknya demi mendapat dana yang banyak pula – dan ini terjadi dengan mereka berusaha menjadi pilihan terbaik bagi orangtua dan anaknya! Kita tidak dapat selamanya mengandalkan pemerintah, karena seringkali pemerintah tidak efektif. Kebiasaan orang Indonesia adalah menuntut dan terus menuntut, tanpa menyadari bahwa sebenarnya yang harus kita tuntut bukanlah campur tangan pemerintah, tetapi kebebasan dari campur tangan berlebihan mereka. Saya berharap, kita segera menyadari hal tersebut, sehingga banyak hal dapat berjalan dengan lebih efektif dan agresif – seperti pasar bebas!