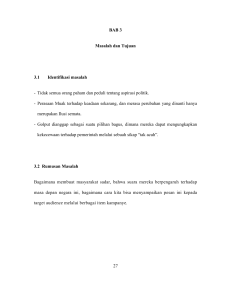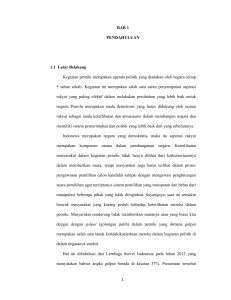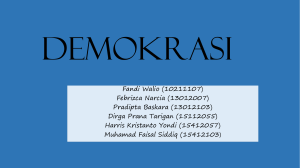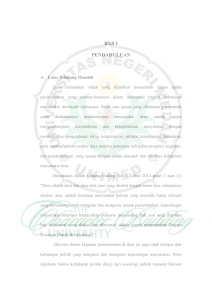Golput dan Pilihan yang Tersisa
advertisement

Golput dan Pilihan yang Tersisa Tamrin Amal Tomagola SUDAH jatuh, tertimpa tangga pula. Demikianlah suasana penuh penderitaan yang mencengkam hati dan pikiran banyak rakyat di negeri kita di tahun politik ini. Bukan hanya bencana alam beruntun: letusan gunung, banjir, dan longsor yang meluluhlantakkan jembatan atau rumah dan sawah/ladang sebagian dari mereka, melainkan juga letusan-letusan megakorupsi di puncak-puncak lembaga negara dan banjir tebar janji-janji politik dusta yang melongsorkan kepercayaan rakyat kepada elite nyaris ke titik dasar. Tergerus sisa-sisa kepercayaan rakyat kepada politisi, partai politik, dan para pengelola negara ini. Dipaksa untuk golput Berbeda dengan status golongan putih (golput) di era Orde Baru yang murni pilihan bebas berdasarkan keyakinan ideologis dan analisis politik rasional; golput dalam sepuluh tahun terakhir—yang proporsinya kian mendekati angka 40 persen—sebagian besar karena dipaksa oleh dua hal. Pertama, kealpaan sistem pendataan. Kedua, tak ada pilihan waras-rasional yang tersisa. Keamburadulan sistem pendataan calon pemilih sudah telanjur menjadi cacat sistemik— walau tidak sistematik—dan kronis yang terus berlanjut tak terpecahkan tuntas dalam sepuluh tahun terakhir. Demikian pula dengan keterpaksaan sebagian rakyat pemilih untuk menjadi golput karena berkelanjutannya realita kualitas mayoritas calon anggota legislatif (caleg) atau karena sebagian besar kandidat presidensial 2014 sama sekali tidak meyakinkan. Keraguan dan ketidakyakinan calon pemilih yang kian mengental ini digelembungkan oleh rekam jejak para petarung politik itu sendiri. Ketiadaan pilihan waras-rasional yang tersisa, yang potensial berujung pada membengkaknya proporsi golput di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, dilandasi paling kurang tiga faktor. Pertama, nyaris 100 persen anggota DPR adalah petahana yang terekam sebagai juara bolos, tukang tidur, dan tunaprestasi; sekitar 90 persen (501 orang) mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPR; dan selebihnya bergeser ke gedung tetangga menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, para caleg ini sama sekali tidak mumpuni dalam hal kapabilitas kompetensi profesional (professional incompetency). Ketunaan kompetensi profesional ini terukur pada (a) rendahnya kemampuan menangkap dan mengagregasikan benang merah kegundahan publik (political aggregation) untuk kemudian diartikulasikan, baik dalam komunikasi politik (political articulation) maupun pilihan-pilihan strategi perundangundangan untuk mengatasi kegundahan publik dan menyelesaikan permasalahan bangsa secara mendasar berkesinambungan; serta (b) rendahnya penguasaan landasan/kerangka konstitusional dan keterampilan perumusan perundang-undangan yang paling elementer di sebagian besar anggota DPR petahana. Rendahnya kapabilitas kompetensi profesional pada akhirnya membuahkan bencana legislasi, yakni: (a) banyak rumusan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK); dan (b) kegagalan kronis dalam memenuhi target legislasi setiap tahun. Ketiga, kerapuhan kompetensi moral-publik (public-morality incompetency) para pejabat publik, khususnya para legislator di Senayan. Tunakompetensi moral publik yang bisa berbeda tetapi bisa juga tumpang-tindih dengan moralitas personal ini terlacak, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat institusional sebagai lembaga. Kian panjangnya daftar legislator yang secara berjejaring menjarah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta betapa luas skalanya—sampai ke perangkat-perangkat internal partai politik—dan begitu mendalamnya cengkeraman jejaring korupsi di hampir semua perangkat kelembagaan DPR, makin memunculkan kekhawatiran publik bahwa DPR sedang bertransformasi menjadi Dewan Penjarah Rakyat. Publik kian terperangah ketika dalam beberapa kesempatan pembahasan dan perumusan perundang-undangan, beberapa koboi Senayan di Komisi 3 DPR berupaya dengan segala cara membonsai dan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yang sangat bernafsu menyunat wewenang KPK ini berargumen bahwa KPK tidak perlu diberikan wewenang luar biasa dan malah tidak perlu ada karena negara sudah punya perangkat kelembagaan pemberantasan korupsi baku yang sudah lama ada. Para koboi Senayan ini mengabaikan fakta bahwa, menurut Transparency International Indonesia, justru lembaga-lembaga baku seperti kejaksaan, kepolisian, dan jajaran pengadilan bersama-sama dengan DPR adalah lembaga-lembaga yang berlumuran dengan korupsi kronis yang sistemik dan sistematik. Menjelang Pemilu Legislatif 9 April, upaya pelemahan KPK terus gencar diupayakan dalam 12 butir Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh pemerintah. Capres yang ditolak Berbeda dengan mayoritas caleg petahana berlabel ”rongsok” yang ditawarkan partai politik kepada calon pemilih 2014, para capres yang nama-namanya sudah beredar luas di publik terdiri atas dua kelompok. Pertama, kelompok capres ”stok lama” yang punya cacat masa lampau dalam bidang hak asasi manusia (HAM), cacat dalam penyengsaraan rakyat di masa kini, dan capres yang ”tunaprestasi” ketika memimpin di masa lampau. Terhadap para capres kategori ini, beberapa jajak pendapat menemukan penolakan publik terhadap sejumlah nama. Kedua, kelompok capres karbitan yang ujuk-ujuk mencalonkan diri tanpa mengukur kapasitas diri, rekam jejak yang telah dibukukan; tanpa kemampuan mengenali dan merumuskan permasalahan-permasalahan utama negara dan bangsa serta tidak siap dengan solusi secara mendasar dan berkesinambungan. Karena karbitan, kelompok capres ini jelas bukan capres yang mekar karena memar dalam karier kepemimpinan masing-masing. Belajar dari penolakan dini dari publik atas sejumlah nama capres, di masa mendatang sebaiknya setiap partai politik berbenah diri secara sungguh-sungguh dalam sistem dan proses pengaderan secara berjenjang dalam struktur kepengurusan partai politik. Seorang kader partai politik harus mau meniti karier politik dari bawah, merangkak secara bertahap, jenjang demi jenjang, yang terus dipantau dan dicatat rekam jejak masingmasing dalam suatu sistem seleksi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Caracara penunjukan oleh ”Bapak Besar” dan oleh ”Ibu Besar” harus dihentikan. Pemilu batal? Upaya penegakan sistem dan proses demokrasi-konstitusional berada di ambang bahaya yang nyata (present and clear danger) jika proporsi mereka yang dipaksa golput dan yang terpaksa golput melebihi tiga perempat dari jumlah penduduk yang berhak memilih pada tahun 2014, baik saat pemilu legislatif maupun saat pemilihan presiden. Mereka yang golput secara ideologis dan berdasarkan analisis politik yang waras dan rasional—terkait kebuntuan yang terakumulasi dalam sistem dan SDM politik, baik di parpol maupun di lembaga-lembaga pengemban demokrasi konstitusional—sudah pasti enggan menuju bilik suara pada 9 April dan 6 Juli nanti. Proporsi golput ideologis ini terbatas di kelas menengah terdidik perkotaan. Mungkin sudah kasep mengubah sikap mereka sampai dengan hari pemungutan suara. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh para manipulator suara, khususnya di tingkat kecamatan. Mereka yang terpaksa golput karena mayoritas caleg adalah petahana dan menolak wajah-wajah di daftar calon presiden, mungkin sekali akan menumpahkan kekesalan mereka sekaligus mencegah manipulasi suara dengan cara mencoblosi semua gambar partai politik dan caleg serta calon presiden yang berlaga. Ini suatu bentuk perlawanan terhadap politisi, partai politik, dan penyelenggara negara. Bagi partai politik yang berhasil melakukan regenerasi caleg dan calon presiden, mereka sebaiknya menonjolkan secara all out wajah-wajah caleg dan calon presiden muda yang terbukti mumpuni dalam hal rekam jejak. Mudah-mudahan para calon golput yang menjadi golput karena alasan terpaksa, mengurungkan niat mereka dan dengan itu kita bersama-sama bukan hanya dapat menyelamatkan Pemilu 2014, melainkan juga menyelamatkan demokrasi konstitusional di negeri tercinta ini. Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia