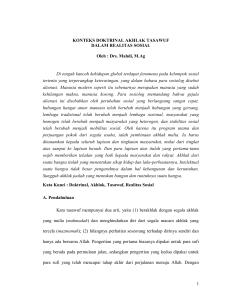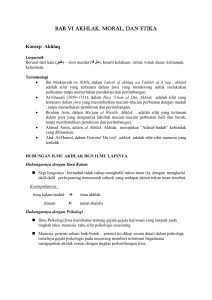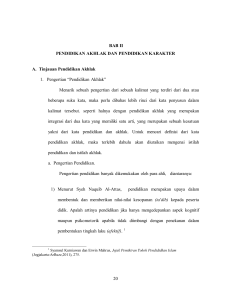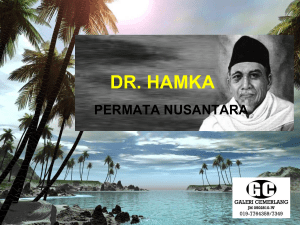ilmu pengetahuan dalam perspektif al-qur`an - E
advertisement
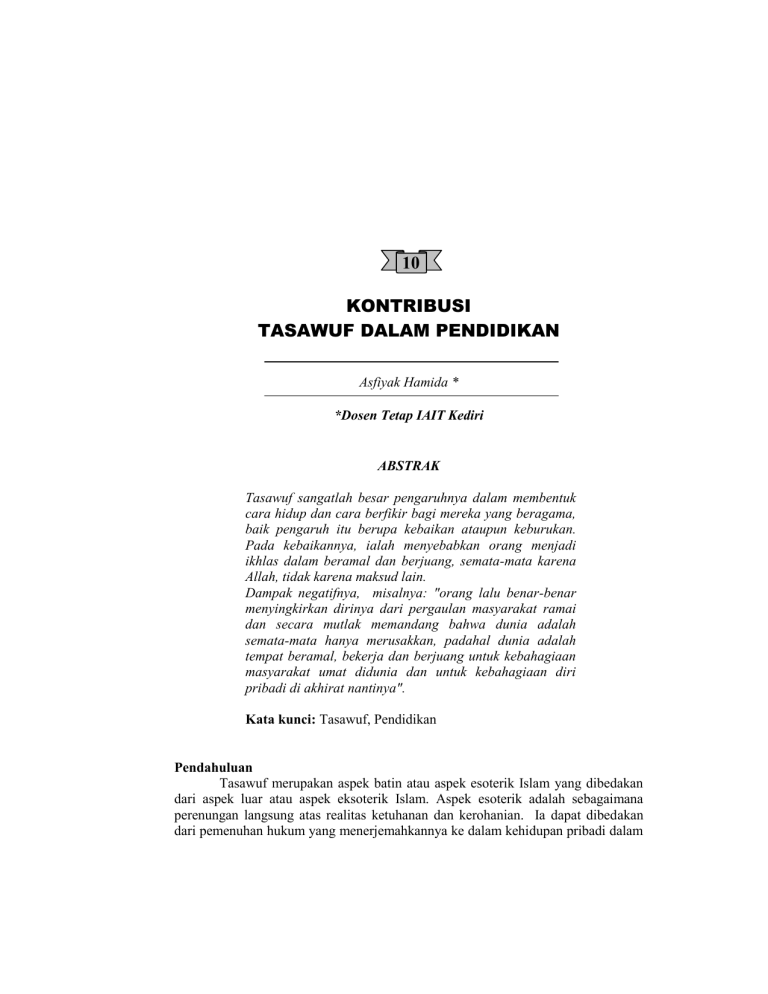
10 KONTRIBUSI TASAWUF DALAM PENDIDIKAN Asfiyak Hamida * *Dosen Tetap IAIT Kediri ABSTRAK Tasawuf sangatlah besar pengaruhnya dalam membentuk cara hidup dan cara berfikir bagi mereka yang beragama, baik pengaruh itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Pada kebaikannya, ialah menyebabkan orang menjadi ikhlas dalam beramal dan berjuang, semata-mata karena Allah, tidak karena maksud lain. Dampak negatifnya, misalnya: "orang lalu benar-benar menyingkirkan dirinya dari pergaulan masyarakat ramai dan secara mutlak memandang bahwa dunia adalah semata-mata hanya merusakkan, padahal dunia adalah tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan masyarakat umat didunia dan untuk kebahagiaan diri pribadi di akhirat nantinya". Kata kunci: Tasawuf, Pendidikan Pendahuluan Tasawuf merupakan aspek batin atau aspek esoterik Islam yang dibedakan dari aspek luar atau aspek eksoterik Islam. Aspek esoterik adalah sebagaimana perenungan langsung atas realitas ketuhanan dan kerohanian. Ia dapat dibedakan dari pemenuhan hukum yang menerjemahkannya ke dalam kehidupan pribadi dalam hubungannya dengan kondisi suatu fase tertentu kemanusiaan. Jalan hidup orangorang beriman pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian, suatu keadaan yang dapat dicapai melalui cara tidak langsung dan keikutsertaan simbolis dalam kebenaran Tuhan dengan melaksanakan perbuatanperbuatan yang telah ditentukan. Sufisme mengandung tujuan dalam dirinya sendiri dengan pengertian bahwa ia dapat memberikan jalan masuk bagi pengetahuan langsung tentang keabadian. Peran ―sentral‖ sufisme pada jantung dunia Islam ini boleh jadi terselubung dari pandangan orang yang mengujinya dari luar karena esoterisme. sementara ia sadar akan arti bentuk-bentuk prakteknya. Pada waktu yang sama berada pada posisi kebebasan intelektual dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk praktek itu. Dengan demikian dapat diasimilasikan pada dirinya —bagaimanapun juga untuk membeberkan ajaran-ajarannya— gagasan-gagasan atau simbol-simbol tertentu yang berasal dari warisan kultur yang berbeda dengan latar belakang tradisionalnya sendiri. Di dalam ajaran-ajarannya tasawuf membicarakan suatu kebenaran yang dari dulu langgeng dan universal, dalam metode-metodenya ia mempergunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kodrat orang-orang abad ini, kodrat yang dalam hakikinya tetap tak berubah dari kodrat manusia masa silam namun yang di dalam kejadian-kejadian dan perwujudan-perwujudan lahirnya telah menjadi lebih kebal terhadap pengaruh-pengaruh keruhanian dan yang di dalam kehidupan kontemplatifnya mengalami kesengsaraan dan kemerosotan.1 Tasawuf secara hakiki memasuki fungsinya dalam mengingatkan kembali manusia siapa ia sebenarnya, yang berarti bahwa manusia dibangunkan dari mimpinya yang ia sebut kehidupannya sehari-hari dan bahwa jiwanya bebas dari pembatasan-pembatasan penjara khayali egonya itu yang memiliki imbangan obyektifnya di dalam apa yang disebut ―kehidupan‖ (dunia) menurut bahasa keagamaan. Dengan menarik ke kodrat manusia yang sebenarnya, tasawuf memenuhi kebutuhan-kebutuhan kodratnya yang nyata, bukan apa yang ia rasakan menjadi kebutuhan-kebutuhannya dilihat dari sudut kesan-kesan dan bentuk-bentuk lahir yang oleh jiwa diterima terus-menerus dari dunia luar ke dalam mana ia telah menanamkan akar-akarnya. Manusia mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya secara lahiriah oleh karena ia tidak mengenal siapa ia sebenarnya. Tasawuf mengingatkan kembali manusia supaya mencari semua yang ia perlukan itu secara batin di dalam dirinya sendiri, supaya mencabut akar-akar kehidupannya yang tertahan di dunia lahiriah dan menanamkannya ke dalam Kodrat Ilahi, yang berada di pusat kalbunya. Tasawuf menarik kembali manusia dari keadaan asfal safilin-nya yang hina dalam rangka mengembalikannya ke dalam kesempurnaan ahsan taqwim-nya yang dahulu di mana ia menjumpai semua yang telah disaksikan secara lahir di dalam dirinya, karena telah menyatu dengan Tuhan maka ia terlepas dari ketiadaan. Ilmu yang melahirkan tasawuf menjelaskan alasan dasar bagi keimanan dan keislaman. Ia berbeda dari kalam dalam perspektif dan fokus, tetapi tasawuf juga tak kalah dalam pijakannya dalam sumber-sumber tradisi itu. Pada tataran praktis, tasawuf memberikan sarana bagi kaum muslim untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman mereka atas Islam untuk menemukan Allah dalam diri mereka sendiri dan dunia. Ia memperkuat kehidupan ritual Islam melalui perhatian seksama pada perincian-perincian sunnah dan pemusatan pikiran pada zikir (dzikr), mengingat Allah setiap saat.2 Tasawuf adalah juga falsafah hidup, yang dimaksudkan untuk meningkatkan jiwa seorang manusia, secara moral, lewat latihan-latihan praktis yang tertentu, kadang untuk menyatakan pemenuhan fana dalam Realitas Yang Tertinggi serta pengetahuan tentang-Nya secara intuitif, tidak secara rasional, yang buahnya kebahagiaan rohaniah, yang hakikat realitasnya sulit diungkapkan dengan kata-kata, sebab karakternya bercorak intuitif, dan subyektif. Tasawuf pada umumnya memiliki lima ciri yang bersifat psikis, moral, dan epistemologis. Kelima ciri tersebut adalah:3 1. Peningkatan moral. Setiap ajaran tasawuf memiliki nilai-nilai moral tertentu yang tujuannya untuk membersihkan jiwa, untuk perealisasian nilai-nilai itu. Dengan sendirinya, hal ini memerlukan latihan-latihan fisik-psikis tersendiri, serta pengekangan diri dari materialisme duniawi, dan lain-lain. 2. Pemenuhan fana (sirna) dalam Realitas Mutlak. Yang dimaksud fana, bahwa dengan latihan-latihan fisik serta psikis yang ditempuhnya, akhirnya seorang sufi sampai pada kondisi psikis tertentu, di mana dia tidak lagi merasakan adanya diri ataupun keakuannya. Bahkan dia merasa kekal-abadi dalam Realitas Yang Tertinggi. Lebih jauh lagi, dia telah meleburkan kehendaknya bagi kehendak Yang Mutlak. Dari sebab inilah sebagian sufi berkeyakinan tentang dapat terjadinya persatuan dengan Realitas Yang Tertinggi itu, atau Yang Mutlak tersebut berada dalam diri mereka. Dengan kata lain, wujud hanya satu, dan bukannya sama-sekali berbilang banyak. Namun sebagian sufi tidak menyatakan pendapat begitu, yakni tentang penyatuan, hulul, atau ketunggalan wujud (wahdatul wujud). Sebaliknya, sekembalinya dari kesirnaan (fana) mereka justru mengokohkan adanya dualitas atau pluralitas wujud. 3. Pengetahuan intuitif langsung. Ini adalah norma terkaji epistemologis, yang membedakan tasawuf daripada filsafat. Apabila dengan filsafat, yang dalam memahami realitas seseorang mempergunakan metode-metode intelektual, maka dia disebut seorang filosof. Sementara, kalau dia berkeyakinan atas terdapatnya metode yang lain bagi pemahaman hakikat realitas di sebalik persepsi inderawi dan penalaran intelektual, yang disebut dengan kasyf atau intuisi maka dalam kondisi begini dia disebut sufi dalam pengertiannya yang lengkap. Intuisi, menurut para sufi, bagaikan sinar kilat yang muncul dan perginya selalu tibatiba. 4. Ketentraman atau kebahagiaan. Ini merupakan ciri khusus pada semua bentuk tasawuf. Sebab, tasawuf diniatkan sebagai penunjuk atau pengendali berbagai dorongan hawa nafsu, serta pembangkit keseimbangan psikis pada diri seorang sufi. Dengan sendirinya, maksud ini membuat sang sufi terbebas dari semua rasa takut dan merasa intens dalam ketenteraman jiwa, serta kebahagiaan dirinya pun terwujudkan. Selain itu, sebagian sufi menyatakan, bahwa pemenuhan fana dalam Yang Mutlak dan pengetahuan mengenai-Nya justru membangkitkan suatu kebahagiaan pada diri seorang manusia, yang mustahil dapat diuraikan dengan kata-kata. 5. Penggunaan simbol dalam ungkapan-ungkapan. Yang dimaksud dengan penggunaan simbol ialah bahwa ungkapan-ungkapan yang dipergunakan para sufi biasanya mengandung dua pengertian. Pertama, pengertian yang ditimba dari harafiah kata-kata. Kedua, pengertian yang ditimba dari analisa serta pendalaman. Pengertian yang kedua ini hampir sepenuhnya tertutup bagi yang bukan sufi, dan sulit baginya untuk dapat memahami ucapan sufi, apalagi untuk dapat memahami maksud tujuan mereka. Sebab, tasawuf adalah kondisi-kondisi efektif yang khusus, yang mustahil dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan ia pun bukan merupakan kondisi yang sama pada semua orang. Setiap sufi punya cara tersendiri dalam mengungkapkan kondisi-kondisi yang dialaminya. Dengan demikian, tasawuf merupakan pengalaman subyektif. Inilah sebabnya tasawuf dekat dengan seni. Khusus para penempuhnya, dalam menguraikan kondisi yang mereka alami, mempergunakan introspeksi sebagai landasan. Dari hal inilah mengapa tasawuf diberi atribut dengan simbolisme. Pengaruh Positif dan Negatif Terhadap Pendidikan Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu. Wahyu mengandung ajaran hubungan antara manusia dan Tuhan. Salah satu aspek yang ditimbulkan ajaran tersebut adalah mistisisme. Mistisisme dalam Islam disebut tasawuf atau, oleh orientalis Barat, disebutnya dengan ―sufisme‖. Sejarah Islam telah melahirkan ajaran tasawuf, di samping ajaran-ajaran lain, yang tumbuh dari jazirah Arab pada abad pertama Hijriah. Dari sanalah, merembes ke berbagai penjuru dunia, dan masuk ke nusantara sejalan dengan masuknya agama Islam. Tasawuf sangatlah besar pengaruhnya dalam membentuk cara hidup dan cara berfikir bagi mereka yang beragama, baik pengaruh itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Pada kebaikannya, ialah menyebabkan orang menjadi ikhlas dalam beramal dan berjuang, semata-mata karena Allah, tidak karena maksud lain. Adapun dampak negatifnya, misalnya: "orang lalu benar-benar menyingkirkan dirinya dari pergaulan masyarakat ramai dan secara mutlak memandang bahwa dunia adalah semata-mata hanya merusakkan, padahal dunia adalah tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan masyarakat umat didunia dan untuk kebahagiaan diri pribadi di akhirat nantinya". Oleh karena itu, seringkali tasawuf dituduh sebagai biang keladi munculnya gerakan a-sosial dan ahistoris dalam masyarakat maupun dunia intelektual. Bagi kalangan ini, tasawuf dianggap hanyalah upaya melarikan diri (eskapisme) dari kenyataan masalah duniawi. Hal ini terjadi karena adanya seorang tokoh sufi yang telah sampai (wusul) kepada ma‘rifat tasawuf —mengandaikan dirinya bila dikaruniai Allah pengalaman isra‘ mi‘raj sebagaimana rasul— maka ia akan berhenti dihadapan Allah dan tidak ingin lagi turun atau kembali ke dunia karena nikmat dan tercapainya tujuan sufi. Banyak alasan mengapa orang tidak menyukai tasawuf. Citra heterodok, yang melibatkan doktrin wihdatul wujud, ittihad dan hulul (shatahat) dianggap sebab utama. Di samping itu, tasawuf dianggap a-politik dan pemikiran tasawuf yang berujung pada kesalehan pribadi itu tidak menyentuh kepekaan dan kepedulian sosial merupakan sebab lain. Belum lagi tuduhan kaum modernis yang menyatakan bahwa praktek-praktek tarekat berubah menjadi penyembahan atau pemuliaan pribadi-pribadi pendiri aliran (cult of personalities). Sesungguhnya berbeda dengan salah seorang sufi tadi, kema‘rifatan rasul bersifat profetis. Artinya beliau dimi‘rajkan untuk kembali lagi ke dunia menjalankan misi kerasulan, antara tauhid dan kemanusiaan. Beliau kembali ke masyarakat untuk sebuah misi dan bukan untuk menghindar dari dunia dan masyarakatnya. Inilah misi rahmatan lil ‗alamin. Tasawuf juga dianggap hanyalah sebuah bentuk hedonisme spiritual yang apatis dan kurang peka terhadap masalah-masalah sosial-kultural yang merupakan penyakit masyarakat. Tasawuf di sini diperas hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan pribadi yang subyektif. Mirip dengan pengertian di atas, di Barat tasawuf digunakan sebagai meditasi dan latihan diri demi mencapai ketenangan jiwa. Dalam masyarakat yang modern di Barat yang dilanda krisis identitas, keterasingan dan stress fungsi tasawuf disamakan dengan yoga. Disikapi secara sekuler dan dipelajari oleh berbagai macam agama, termasuk selain Islam. Dalam hal ini, tasawuf tereduksi dan terjadi pendangkalan spiritualitas. Sedangkan mistikisme adalah suatu tipe dalam agama yang menekankan adanya hubungan langsung dengan Tuhan. Dan disadari benar bahwa Tuhan hadir dalam dirinya. Mistikisme muncul di dunia kristen dalam gerakan dan tulisan-tulisan Dionisius Aeropagita pada abad kelima Masehi. Dalam Islam, mistikisme mengambil bentuk sufisme.4 Untuk memperoleh ilmu, sufisme menolak rasionalitas dan tangkapan indera (empirik). Sumber ilmu pengetahuan untuk mencapai ma‘rifat menurut mereka melalui dzawq, atau hadsiy, atau a’yan, atau kasyf, atau wujdan, yaitu intuisi. Kritik Iqbal dilancarkan pada mistikisme Barat maupun Timur dengan kritikan yang amat pedas dan tidak simpatik. Demikian kritik Iqbal: ―Tata cara mistikisme abad pertengahan yang oleh kehidupan religius, pada tingkat perwujudannnya yang lebih tinggi, dikembangkan di Timur maupun di Barat secara praktis menemui kegagalan. Mistikisme dalam Islam di Timur, dalam berbagai aspeknya, lebih banyak merusak‖.5 Memang di bawah sufisme –minimal pada saat Iqbal menyaksikan praktekpraktek mereka di India— Kaum sufis menyebarkan berbagai keyakinan dan praktek-praktek syirik di kalangan masyarakat. Mereka sering melakukan kurban di makam para wali. Kaum wanita melakukan puasa diniatkan untuk para guru sufinya. Para sufi sering melakukan puasa dengan niat tidak berbuka, kecuali dari hasil meminta-minta. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya disertai ritus-ritus tertentu. Menurut Iqbal, andil pemikiran idealisme Plato terhadap sufisme amat kental. Untuk itulah ia merintih; "O Tuhan ….orang-orang sucimu senang dengan keadaan psikis mereka. Artinya, kaum sufi hanya asyik dengan kehidupan rohani dan kurang memperhatikan kehidupan sosial kemasyarakatan.6 Seringkali kaum sufi mendapat kecaman dan kritik pedas, disebabkan sikap radikal mereka terhadap syari‘at. Kaum sufi dianggap sering meremehkan perintah syariat, bahkan ada yang secara radikal meninggalkan syari‘at sama sekali. Sebaliknya kaum syari‘at menganggap bahwa di dalam syari‘at sudah termaktup jalan tasawuf. Sehingga tidak perlu repot-repot mencari tasawuf. Disamping itu, pemikiran-pemikiran puncak kaum sufi terformulasikan dalam doktrin hulul, ittihad dan wihdatul wujud yang oleh para ulama dianggap sudah terlalu jauh dari pagar batas Islam. Contoh kasus pemasungan tokoh sufi besar Mansur al- Hallaj dengan doktrin hululnya serta pembunuhan tokoh sufi Persia yang lain, Shahab al-Din Shuhrawardi pendiri aliran Illuminationism merupakan contoh konkret dalam sejarah peradaban Islam.7 Sungguh pun demikian, kenyataan sosial menunjukkan bahwa (1) kalangan santri (bahkan dari kalangan intelek santri) masih tetap menyenangi ‗tarekat‘ (Kasus Pondok Pesantren Suryalaya). (2) di kalangan ‗abangan‘ (kita akui bahwa klasifikasi ini tidak setepatnya mewakili keadaan yang sesungguhnya hidup dan berproses di tanah air), justru menyuburkan aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika dipolakan secara garis besar, keadaan tasawuf di Indonesia ada 2 macam: 1. Pola tasawuf yang berorientasi kepada kepuasan subjektif, yaitu seperti yang dilaksanakan dikalangan tarekat-tarekat rata-rata –namun bukan berarti mutlak seluruhnya— dan dalam aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pola tasawuf yang berorientasi kepada kepuasan amal sosial (etika sosial), yaitu seperti yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah.8 Tasawuf, ibaratnya adalah seperti ‗magnit‘. Dia tidak menampakkan diri dipermukaan, tapi mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Potensi itu dapat dimanfaatkan untuk apa saja. Dalam kehidupan modern yang serba materi, tasawuf bisa dikembangkan ke arah yang konstruktif, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Orang butuh pedoman hidup yang bersifat spiritual yang mendalam untuk menjaga integritas kepribadiannya. Perdebatan tentang tasawuf — atau sufisme dengan memakai istilah Barat— nampaknya belum akan segera berakhir. Perdebatan ini tak pelak telah melestarikan pertikaian berabad-abad antara orientasi batin (esoteris) dan lahir (eksoteris) dalam hidup keagamaan. Sepanjang sejarah pemikiran Islam, beberapa rumusan sintesis pernah diupayakan guna mengatasi pertentangan ini. Namun tak lama kemudian, divergensi kembali terbentuk dalam kecenderungan ekstrim kepada salah satu kutub. Akibatnya, panorama pemikiran Islam, tak terkecuali di bidang tasawuf, pekat dengan ketegangan dan tantangan, namun juga usaha-usaha yang sama gigihnya untuk mengatasi ketegangan dan tantangan. Suatu dinamika yang agaknya terus berlanjut hingga sekarang. Dimulai dari Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim, gerakan reformasi keagamaan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Tujuan utama dari gerakan tersebut, seperti dirumuskan Ibnu Taymiyyah, adalah pernyataan kembali Syari‘ah sebagai konsep yang komprehensif, mencakup kebenaran spiritual (haqiqah) kaum sufi, kebenaran rasional (‗aql) para filosof dan teolog dan hukum. Hal ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap polarisasi disiplin keilmuan Islam yang saling terisolasi dan beroposisi satu sama lain.9 Mengenai tasawuf, gerakan ini masih dapat menerima klaim validitas metode eksperimental sufi. Namun sementara itu ritus-ritus sufi dan praktek-praktek pemujaan makam serta pengkultusan wali-wali diserang habis-habisan. Menurut mereka, meskipun pengalaman sufi sebagai pengalaman riil, namun pengalaman tersebut tidak memiliki validitas eksklusif, sebaliknya harus diuji dengan rujukan dunia luar. Dengan kata lain, kalangan ini menghendaki obyektivasi dari pengalaman sufi.10 Di dalam kancah pemikiran lslam modern, pembaruan tasawuf mendapatkan formulasinya yang lengkap di kalangan para pemikir neo-modernis. Aliran ini, seperti dirintis oleh Fazlur Rahman, memiliki semangat pembaruan kaum modernis, namun sekaligus berpijak kukuh pada khazanah tradisi klasik. Pembaruan tasawuf oleh kalangan ini, sejajar dengan nama alirannya, dikenal luas dengan sebutan neosufisme. Neo-sufisme adalah sejenis kesufian yang merupakan kelanjutan dari ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam al-Qur‘an dan Hadits, serta berada dalam pengawasan kedua sumber utama ajaran itu, dengan ketentuan untuk tetap menjaga keterlibatan dalam masyarakat secara aktif. Sejajar dengan al-Ghazali, kesufian ini memberikan apresiasi yang wajar kepada penghayatan esoteris dan sementara itu menekankan esoterisme agar tetap berada dalam kendali ajaran standar Syari‘ah. Bedanya adalah, sedangkan al-Ghazali cenderung pada pengasingan atau ‗uzlah, neo-sufisme tetap menekankan obyektivasi dan aktivisme dalam realitas luar.11 Secara epistemologis, aliran ini dapat menerima kebenaran klaim sufisme intelektual mengenai kasyfi (pengalaman penyingkapan kebenaran ilahi) atau ilham intuitif. Hanya saja menolak klaim seolah-olah kasyfi tidak dapat salah, dengan menekankan bahwa kehandalan kasyfi sebanding dengan kebersihan moral dari kalbu, yang sesungguhnya mempunyai tingkat-tingkat yang tak terhingga. Kasyfi yang disebut Fazlur Rahman sebagai akal perseptif tidaklah ditolak. Yang ditolak adalah, jika akal perseptif tersebut diputuskan hubungan organisnya dengan akal formulatif.12 Neo-sufisme dengan demikian berusaha menerapkan secara konsisten prinsip keseimbangan (tawazun) dan moderasi (tawasuth), pertama-tama antara dimensi esoteris dan eksoteris —Thariqah dan Syari‘ah, kemudian antara orientasi duniawi dan ukhrawi, keselamatan individual dan sosial, dan akhirnya antara nilai rasa (dzawq) dan rasio. Ini sejajar dengan semangat ekuilibrium yang dirintis semenjak Ibnu Taymiyyah.13 Berbeda dengan kalangan neo-modernis, Simuh (Guru Besar Tasawuf pada Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga) menilai tasawuf dari perspektif negatif. Suatu tilikan yang melihat tasawuf bukan dari sejauh mana ia dapat mengintegrasikan diri ke dalam struktur bangunan ortodoksi. Melainkan, secara negatif, sejauh mana tasawuf tidak mengandung usur-unsur heterodoksi. Dengan Namun hal itu sekaligus memperlihatkan posisi seorang modernis yang gigih, dengan agenda utama pemurnian (purifikasi) tauhid melalui gerakan ‗kembali kepada Al-Qur‘an dan Sunnah‘. Posisi ini, dalam kategori William C. Chittick, mewakili pandangan teolog yang berkeyakinan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui wahyu al-Qur‘an, dan bahwa intelek para filosof dan penyingkapan (kasyf) para sufi cenderung menyesatkan.14 Analisis Simuh mengenai perkembangan tasawuf dengan jelas memperlihatkan perspektif teologis yang kental. Menurutnya, dalam sufisme terkandung aspek akidah yang selama ini justru luput dari pengamatan para peneliti dan pengkaji Islam. Sufisme sebagai suatu paham atau pendekatan ternyata telah memunculkan dan mengembangkan konsep-konsep akidah yang amat canggih dan berpengaruh dominan dalam bangun keyakinan umat Islam. Konsep-konsep itu meliputi dokrin-doktrin teologi, kosmologi, psikologi, epistemologi dan eskatologi yang secara langsung bertentangan dengan kepercayaan tauhid yang jernih dan rasional.15 Bertolak tinjauan semacam ini, pemikiran tersebut terlihat sangat orisinal. dari sini, kalangan modernis cenderung untuk menolak sama sekali klaim legitimasi tasawuf. Pada Prof. Dr. Simuh, penolakan itu juga berlaku bahkan terhadap gerakan reformasi tasawuf, suatu gerakan yang nantinya memunculkan neo-sufisme. Setiap upaya ‗menjinakkan‘ tasawuf pada akhirnya akan sia-sia. Karena tetap tidak bisa mengelak dari hakikat sufisme beserta dasar pikiran yang menjadi tiang tegaknya.16 Apa yang menjadi hakikat sufisme adalah suatu keyakinan (akidah) mengenai kesanggupan segolongan orang pilihan untuk berhubungan langsung (mubasyarah) dengan Tuhan melalui pengalaman kejiwaan yang disebut kasyf. Pengalaman kasyfi ini inheren dalam setiap pengalaman tasawuf; boleh dikata identik dengan tasawuf iu sendiri. Tanpa pengalaman kasyfi tidak ada yang dapat disebut tasawuf. Bahkan reformasi tasawuf yang disebut neo-sufisme, seperti yang telah kita lihat, tidak dapat mengelakkan prinsip dasar ini. Padahal, dalil kasyfi selalu menimbulkan akidah yang neko-neko, seperti paham ketuhanan wujudiyyah, ittihad dan hulul, teori penciptaan teofani dan emanasi, yang kesemuanya berujung pada muara yang sama, yaitu panteisme. Berbagai jenis heterodoksi dalam tasawuf inilah yang menjadi alasan prinsipil bagi kalangan modernis untuk, secara definitif, menolak tasawuf sebagai ungkapan keagamaan yang otentik.17 Persoalan pokok yang senantiasa menjadi fokus utama dalam pro-kontra tasawuf adalah mengenai tendensi panteistik dalam tasawuf. Perdebatan dari kedua belah pihak seringkali justru tambah memperkeruh persoalan ketimbang menjernihkannya.Ini boleh jadi terkait dengan ambang batas ortodoksi dan panteisme yang selalu samar-samar, peralihannya tidak tegas namun gradual, dan ekspresinya saling menumpuk dan berpenetrasi. ketakjelasan semacam ini sering menggelincirkan pengamat pada penilaian sepihak akibat keterbelengguan pada sudut perspektif. Pendekatan negatif yang dilakukan Prof.Dr. Simuh sebagai misal; sementara di satu pihak sangat kritis terhadap unsur panteisme dalam tasawuf, di pihak lain batasan ortodoksi sendiri tidak pernah ditegaskan. Apa yang disebutnya sebagai kemurnian tauhid lebih banyak diasumsikan ketimbang dijelaskan. Akibatnya, pendekatan ini tidak dapat berlaku adil terhadap kehidupan tasawuf karena terjebak pada generalisasi berlebihan, di samping terlanjur kehilangan simpati. Tidak heran jika sampai muncul komentar semacam ini: ―Kaum theis pernah dipersalahkan (dan memang tidak tanpa alasan), bahwa mereka teramat mudah memerikan pantheisme sebagai sistem yang mengadakan identifikasi antara Tuhan dan manusia‖.18 Untuk memperjernih masalah ini, pertanyaan yang perlu diajukan adalah: dalam pengertian apa panteisme itu dimaksudkan. Apakah identifikasi Tuhan dengan alam itu berarti kontinuitas substansial antara Tuhan dan alam, yang berarti suatu imanensi total. Ataukah bahwa tatanan yang nampak ini diidentikkan secara essensial dengan Prinsip Ontologisnya. Apabila arti terakhir ini yang diacu maka transendensi tetap tegak dan ortodoksi dapat dipertahankan. Pada kenyataannya, banyak unsur panteistik yang dituduhkan kepada para sufi ternyata berdasarkan pengalaman pribadi mengenai keesaan Allah yang imanen dan transenden sekaligus. Kemenduaan dalam pengalaman sufi ini memang sering benar menimbulkan kesalah-pahaman di kalangan orang luar.19 Sebenarnya, panteisme sendiri tidak pernah terjadi selama mengenai Tuhan dan alam diakui adanya jurang antara Ada yang mandiri dan ada yang serba terbatas. Dengan kata lain, sejauh analogi dalam cara berada (analogia entis) tetap dipertahankan. Sekalipun sama-sama memiliki konsep Ada, Tuhan dan alam dibedakan secara ketat: Tuhan adalah Ada mandiri, ―ens a se‖ (wajib al-wujud), dan alam adalah ada tergantung, ―ens ab alio‖ (mumkin al-wujud).20 Dalam batasan ini, maka ortodoksi tidak terbatas pada kalam (teologi) belaka, dan apalagi fiqh. Apa yang disebut Sachiko Murata sebagai ‗tradisi kearifan‘ (sapiential tradition), lebih-lebih memiliki segala hal yang dapat diklaim sebagai ortodoksi. Sebab, tradisi ini mendasarkan diri pada relasi polar antara pasanganpasangan (azwaj) yang menghasilkan ekuilibrium segala sesuatu. Dengan demikian dapat dihindarkan kecenderungan yang picik pada satu kutub realitas tertentu. Polaritas Tuhan misalnya, dipahami sebagai kesetimbangan antara aspek Ilahiah jalal (kekuasaan, maskulinitas dan transendensi) dan aspek Ilahiah jamal (keindahan, feminitas dan imanensi), yang akhirnya terjalin satu dalam kamal (kesempurnaan).21 Meskipun polaritas di atas hendak meneguhkan ekuilibrium, namun karena struktur polar itu sendiri selalu bermakna ganda, maka pengungkapannya hanya dapat dilakukan secara paradoks, di mana dualitas dinyatakan serentak dan sejajar (coincidentia oppositorum). Di sinilah kesalahpahaman itu sering terjadi. Struktur berdimensi dua dalam ungkapan sufi selalu menggoda setiap pembaca untuk memasukkan lebih banyak filsafat ke dalamnya daripada yang sesungguhnya dimaui pengarang. Ibaratnya seperti hendak mengail lebih banyak daripada yang terdapat dalam kolam. Harus diingat bahwa kaum sufi tidak hendak berusaha menyusun sistem filsafat. Pernyataan yang mereka buat lebih merupakan ungkapan religius yang bersifat prakonsepsi. Pernyataan tersebut sudah tentu tidak dapat demikian saja diperikan sebagai panteisme —sebagaimana ditegaskan Nicholson— kecuali jika mereka sendiri menggubah perasaannya itu menjadi sistem pemikiran. Dan bahkan jika mereka memang melakukannnya, hasilnya tetap dapat diperdebatkan tanpa harus bersikap a priori dulu terhadapnya. Dalam menghadapi persoalan ‗kebahasaan‘ semacam ini metode pendekatan yang dipakai akan sangat menentukan. Kajian semantik kiranya dapat berbuat adil terhadap tasawuf, di samping mampu mengungkapkan makna batinnya yang tersembunyi di balik ungkapan-ungkapan puitis bahkan eksotis. Salah satu contoh terbaik penerapan metode ini dalam kajian tasawuf adalah tulisan Michael Sells tentang kesatuan mistik dalam Islam.22 Penutup Sebagai catatan akhir, tulisan ini sebegitu jauh tidak mendapatkan kemungkinan untuk menggeneralisir tasawuf sebagai panteisme (shatahat). Tasawuf sebaliknya dilihat sebagai salah satu manifestasi Islam yang otentik. Bahkan jika unsur panteisme itu memang benar-benar ada —hal ini masih bisa diperdebatkan— maka yang harus dilakukan adalah menjernihkan tasawuf dari unsur-unsur penyimpangan itu, dan bukan malah menolaknya sama sekali.23 Selanjutnya, pembicaraan tentang hubungan tasawuf dengan pendidikan, (terutama dalam contoh kasus) dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengacu kepada pembicaraan peranan NU melalui salah satu pendukung utamanya, yaitu pesantren yang merupakan penjabaran real sistem pendidikan dalam tasawuf. Oleh karena itu, melalui pesantren, tasawuf maju pesat di Indonesia sejak dahulu hingga kini. Pesantren memiliki peranan menentukan dalam bidang pendidikan. Tidak dapat dibayangkan keadaan pendidikan pada umumnya dan agama khususnya bagi masyarakat Indonesia tanpa adanya pesantren ini dan bagaimana mereka dapat memainkan peran yang diinginkan karena pesantren umumnya di daerah pedesaan yang merupakan 80% dari jumlah penduduk Indonesia.24 Kenyataan yang dapat dirasakan bahwa pesantren memiliki peran berkesinambungan dalam mengemban tanggung jawab pendidikan masyarakat dan melestarikan ajaran-ajaran Ahl Al-Sunnah wa Al- Jama‘ah. Bukti mengenai hal ini tiada yang lebih nyata dari terdapatnya pesantren di beberapa wilayah yang jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah-sekolah negeri yang menyebabkan banyaknya buta huruf latin dibanding dengan huruf Arab dikarenakan pengajaran Al-Quran lebih diutamakan daripada pengajaran abjad latin.25 Para peneliti Indonesia dan orientalis menegaskan pentingnya peran pesantren bagi pendidikan. Orientalis Waldemar Stohr mengatakan, sesungguhnya pesantren dengan bermacam-macam nama sesuai dengan tempat, ia berada dan tersebar di berbagai pelosok Indonesia, telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup keislaman bagi masyarakat Indonesia melalui pendidikan internal. Seperti diketahui, pesantren sejak awal pendiriannya memiliki sistem kehidupan yang berbeda dengan lingkungan sekitar, antara lain pesantren menawarkan pengajaran ilmu-ilmu agama dan nilai-nilainya dari segala aspek dengan pemusatan pada penerapan ilmu-ilmu dan nilai-nilai tersebut dengan mengharap ridha Allah Swt. dan Rasul-Nya.26 Pada awal berdirinya, pesantren memperkenalkan suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di lingkungan setempat, kemudian terjadi interaksi antara kedua kebudayaan tersebut, dan yang pertama mempengaruhi yang kedua sehingga dalam perkembangannya masyarakat menjadi bagian dalam kebudayaan tersebut dan loyal kepadanya. Seterusnya pengaruh pesantren dalam mengubah gaya hidup yang menempatkan nilai-nilai Islam menggantikan nilai-nilai yang sebelumnya berpengaruh di daerah itu, sebelum adanya pesantren.27 Keberhasilan ini umumnya kembali kepada keikhlasan dan dedikasi kiai atau mursyid demi perjuangan dakwah Islam dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Untuk itu ia harus menjadi teladan dan panutan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali ridha Allah Swt. dan Rasul-Nya. Bahkan terkadang kiai terlebih dahulu harus mengorbankan harta kekayaannya dalam membangun pesantren semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt. Oleh sebab itu, Allah Swt. memberkati usaha mereka sehingga ada diantaranya yang berhasil mendirikan ratusan cabang yang terkadang menjangkau wilayah atau pulau terpencil. Usaha para kiai akan terus dan masih terus berlanjut dengan izin Allah Swt. dalam mempertahankan Indonesia tetap sebagai negara Islam dalam menghadapi aliran-aliran yang menyesatkan.28 Endnote 1 Sayyid Husein Nasr, Tasawuf Dulu Dan Sekarang, Terj. Abdul Hadi WM., (Jakarta Pustaka Firdaus, 1985), Cet.I, h. 28. 2 William C. Chittick, Tasawuf dimata Sufi, diterjemahkan dari sufism : A. Short Introduction, (Bandung : Mizan, 2002), 49-50. 3 Abu al-wafa‘ al-Ghanini al-Taftazani (selanjutnya disebut al-Taftazani), Sufi Dari Zaman ke Zaman, Terj. Ahmad Rofi‘ ―Utsmani, (Bandung: Pustaka, 1997), Cet.II, h. 4-7. 4 Danusiri, Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), h. 30. 5 Ibid., h. 31. 6 Ibid., h. 31-32. 7 M. Amin Abdullah, ―Tinjauan Antropologi-Fenomenologis Keberagamaan Manusia: Pendekatan Filsafat untuk Studi Agama-agama‖ dalam Abdurrahman, dkk (ed), 70 Tahun H.A. Mukti: Agama Dan Masyarakat, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), h. 154. 8 Ibid., h. 157. 9 M. Shohibuddin ―Pro-Kontra Tasawuf Dalam Pemikiran Islam‖, dalam Wacana Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Ushuluddin No. 02/II/Juni/1997, h.18. 10 Ibid. 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid., h. 18-19. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Ibid. 20 Ibid., h. 19-20. 21 Ibid. 22 Ibid. 23 Ibid. 24 Dr. Alwi Shiwab, Islam Sufistik: ―Islam Pertama‖ dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia, Pentj. Dr. Muhammad Nursamad, (Bandung: Mizan, 2001), h. 214. 25 Ibid., h. 214-215. 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid.