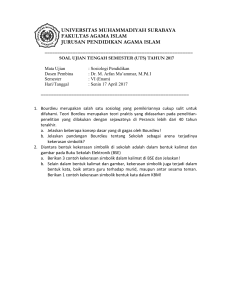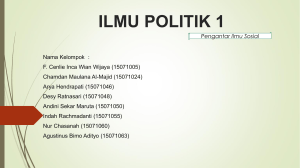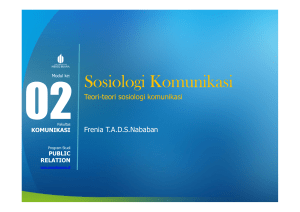BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Penelitian
advertisement
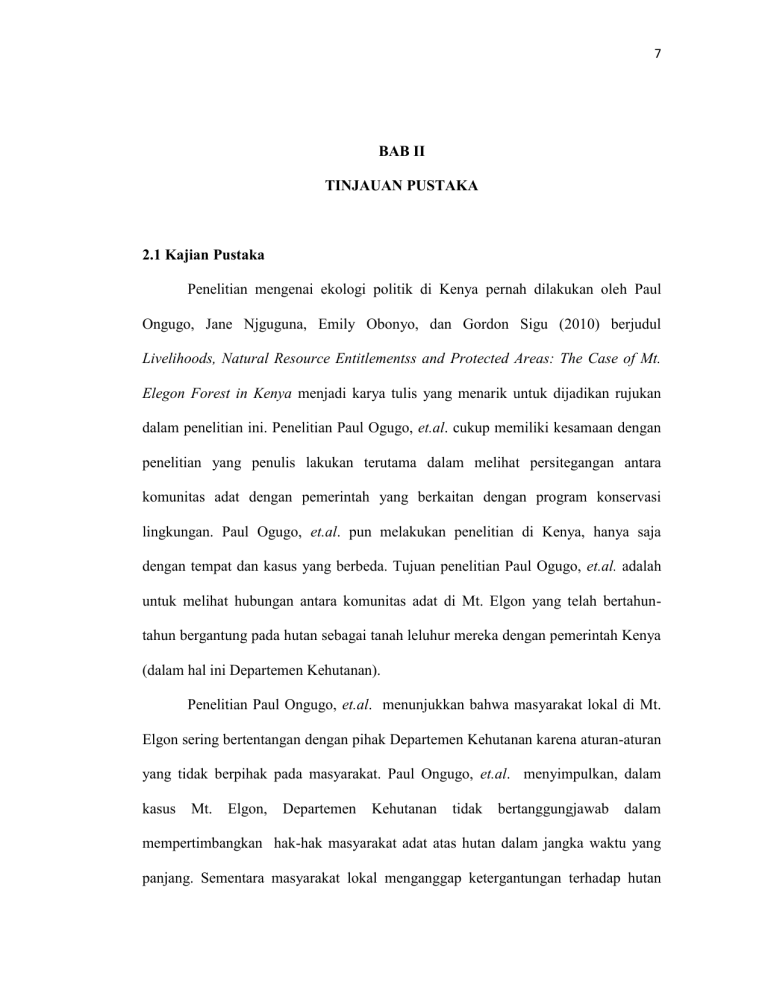
7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Penelitian mengenai ekologi politik di Kenya pernah dilakukan oleh Paul Ongugo, Jane Njguguna, Emily Obonyo, dan Gordon Sigu (2010) berjudul Livelihoods, Natural Resource Entitlementss and Protected Areas: The Case of Mt. Elegon Forest in Kenya menjadi karya tulis yang menarik untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian Paul Ogugo, et.al. cukup memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terutama dalam melihat persitegangan antara komunitas adat dengan pemerintah yang berkaitan dengan program konservasi lingkungan. Paul Ogugo, et.al. pun melakukan penelitian di Kenya, hanya saja dengan tempat dan kasus yang berbeda. Tujuan penelitian Paul Ogugo, et.al. adalah untuk melihat hubungan antara komunitas adat di Mt. Elgon yang telah bertahuntahun bergantung pada hutan sebagai tanah leluhur mereka dengan pemerintah Kenya (dalam hal ini Departemen Kehutanan). Penelitian Paul Ongugo, et.al. menunjukkan bahwa masyarakat lokal di Mt. Elgon sering bertentangan dengan pihak Departemen Kehutanan karena aturan-aturan yang tidak berpihak pada masyarakat. Paul Ongugo, et.al. menyimpulkan, dalam kasus Mt. Elgon, Departemen Kehutanan tidak bertanggungjawab dalam mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat atas hutan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara masyarakat lokal menganggap ketergantungan terhadap hutan 8 sebagai hak mereka, Departemen Kehutanan menganggap bahwa itu merupakan hak hukum mereka. Paul Ongugo, et.al. juga mendapatkan bahwa masyarakat adat di Mt. Elgon tidak memiliki akses yang memadai dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Hal itu menyebabkan pada tahun 2005 terjadi bentrokan oleh masyarakat adat di Mt. Elgon karena penggusuran dilakukan oleh Departemen Kehutanan yang juga menyebabkan kematian beberapa masyarakat adat di sana. Pandangan masyarakat adat di Mt. Elgon berubah terutama karena hak atas kawasan tersebut pernah menjadi milik masyarakat setempat, namun kemudian dilembagakan oleh pemerintah. Masyarakat setempat memiliki respon negatif terhadap konservasi strategi pemerintah. Hal ini yang membuat konflik antara kedua pihak semakin meningkat. Paul Ongugo, et.al. kemudian menyimpulkan pemerintah hanya dapat berhasil dalam melakukan konservasi jika masyarakat lokal memahami kepentingan masing-masing. Untuk itu, ada kepentingan bagi kedua pihak untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Ini juga yang luput diperhatikan pemerintah dalam kasus Mt. Elgon. Berdasarkan temuan-temuan itu, Paul Ongugo, et.al. dalam penelitiannya juga menilai otoritas Kenya harus memberikan masyarakat setempat hak-haknya atas hutan mereka, tetapi juga pada saat yang sama tetap memastikan bahwa tidak terjadi perusakan hutan. Terlebih lagi hutan adat Kenya adalah rumah bagi banyak masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam. Bila pemerintah tidak bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan alasan konservasi sekalipun, justru akan mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. 9 Penelitian Paul Ongugo, et.al. memiliki relevansi dengan penelitian penulis terutama karena perbedaan persepsi konservasi antara pemerintah dengan masyarakat adat. Akan tetapi, Paul Ongugo, et.al. tidak menyebutkan dengan jelas nama program konservasi yang dijadikan fokus penelitian. Penelitian Paul Ongugo, dkk. juga hanya melihat ketegangan terkait pengelolaan hutan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini adalah melihat perjuangan masyarakat adat Sengwer yang dihubungkan dengan konsep gerakan sosial baru – dengan analisis yang lebih umum terkait ekologi politik di negara berkembang. Selanjutnya, tulisan tentang bagaimana masyarakat atau komunitas sosial menyikapi isu ekologi di Kenya pernah ditulis oleh MacKenzie (1998) dalam bukunya berjudul Land, Ecology and Resistance in Kenya. Mackenzie meneliti dialektika perbaikan ekologi di Kenya dan dampak sosialnya terhadap masyarakat Afrika. Melalui buku ini, tujuan khusus yang ingin dicapai Mackenzie adalah untuk menguji antagonisme kelas dan jenis kelamin yang muncul atas wacana perbaikan ekologi tersebut. Hal itu disampaikan pada bagian pertama buku ini, yaitu mencuatnya isu gender terutama ketika pemberontakan perempuan meletus pada 14 April 1948 di Distrik Muranga, Kenya. Pemberontakan itu dilakukan untuk memprotes penggunaan tenaga kerja dipaksa untuk tindakan konservasi tanah negara. Tiga bab pertama meneliti peran perempuan di Muranga, Kenya Pusat, di era pra-kolonial sebagai penggarap pertanian primer; dan bagaimana peran ini berubah ketika Inggris mulai mendefinisikan hukum adat. Hak pra-kolonial atas tanah yang dinamis dan kompleks, meninggalkan ruang untuk negosiasi hak-hak perempuan atas 10 tanah. Redefinisi hukum tanah adat oleh Inggris secara efektif telah menekan hak-hak perempuan atas tanah. Meskipun perempuan yang sebelumnya bisa secara teknis tidak memiliki tanah, hak mereka atas tanah dijamin melalui pengakuan dari nilai mereka sebagai peladang Paham environmentalisme pun mulai masuk ke Kenya sejak itu. Kampanye tahun 1930-an dan 1940-an juga menyusun kembali krisis politik atas tanah sebagai masalah. Masuknya pengetahuan Barat terkait pertanian telah menempatkan praktek pertanian tradisional sebagai tidak ilmiah. Karena kebiasaan masyarakat menempatkan perempuan sebagai pengelola tanah pertanian di Afrika, pengetahuan Barat justru mensyaratkan pembungkaman suara perempuan. Kampanye perbaikan ekologi ketika itu mengurangi status perempuan sebagai penggarap utama tanah dan penjaga pengetahuan pertanian. Pemerintahan kolonial Inggris berusaha untuk menentukan hukum tanah adat yang lebih jelas, dengan mata ke arah perumusan kebijakan. Upaya ini menghasilkan sistem pengelolaan tanah pertanian menjadi kaku dan statis. Akibatnya, sistem hukum adat justru melemahkan posisi perempuan dan kaum miskin oleh para petani kaya atau "Big Men”. Ketegangan yang mendasari antara Mbari (sub-klan) dan individu atau antara perempuan dan laki-laki akan menjadi jauh lebih bermasalah karena tanah menjadi langka di bawah kolonialisme. Mackenzie menunjukkan bahwa di Kiambu, hal ini telah terjadi. Karena dampak dari perdagangan jarak jauh di bagian selatan Kikuyuland selama abad kesembilan belas, solidaritas Mbari telah memberikan cara untuk meningkatkan individualisasi pada saat penaklukan Inggris. Upaya Inggris 11 untuk menentukan hukum tanah adat memperburuk ketegangan yang mendasari sistem tanah adat. Sebagai contoh, karena hak-hak alokasi hutan Mbari menjadi terkontrol. Diferensiasi sosial tinggi dan meningkatnya penjualan tanah mengancam solidaritas sub-klan. Bagian kedua dari buku ini membahas dampak kampanye perbaikan ekologi pada basis sumber daya dan pengetahuan pertanian perempuan. Menurut Mackenzie, keprihatinan atas kerusakan lingkungan menyimpan motif tersembunyi. Pada akhir tahun 1930-an, pemukim Eropa mengkhawatirkan keberhasilan Afrika dengan produksi jagung. Pemerintah kolonial menjadi khawatir akan pertumbuhan Aftika yang cepat. Maka, solusi yang kemudian dibuat adalah dengan menyalahkan orangorang Afrika. Metode pertanian lokal dijadikan penyebab masalah degradasi lahan. Akibatnya, kampanye perbaikan ekologi diartikulasikan lewat metode yang melibatkan pengetahuan atau teknik Barat. Buku ini memberikan gambaran bahwa permasalahan ekologi di Kenya merupakan masalah sejak era kolonial. Demikian juga ketegangan masyarakat (adat) dengan pemerintah terkait manajemen pengelolaan lahan. 1.6 Kerangka Konseptual Salah satu tujuan konsep penelitian adalah untuk mengonfirmasi dan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam permasalahan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan konsep masyarakat adat dan gerakan simbolik kultural; konsep 12 marginalisasi; konsep developmentalisme; dan teori ekologi politik di negara berkembang. 2.1.1 Konsep Gerakan Simbolik Kultural dan Masyarakat Adat Gerakan simbolik kultural adalah salah satu bentuk gerakan sosial baru (Trijono, 2006). Untuk memahaminya, gerakan simbolik kultural ini saling terkait dengan gerakan sosial baru sebagai payungnya. Gerakan sosial (social movement) merupakan salah satu subjek penting dalam ilmu-ilmu sosial. Gerakan sosial senantiasa mendapat tantangan baru dan dituntut memberikan jawaban serta jalan keluar praksis dari permasalahanpermasalahan sosial kontemporer. Demikian pula kemunculan Gerakan Sosial Baru (new social movement – selanjutnya disingkat GSB) sebagai perkembangan Gerakan Sosial Lama (old social movement – selanjutnya disingkat GSL). Bila GSL menekankan aktualisasi pemisahan diri dari determinasi kelas, maka GSB lebih memfokuskan gerakannya dalam isu-isu HAM, identitas, lingkungan hidup, dan pemenuhan layanan (Kurniawan & Puspitosari, 2012). Gerakan simbolik kultural sebagai salah satu bentuk GSB secara operasional muncul sebagai respon atas perubahan nilai atau asas dasar dalam suatu masyarakat. Kurniawan dan Puspitosari (2012) menjelaskan, dalam GSB terdapat kekaburan kekuatan kolektivitas sehingga gerakannya menjadi tersegmentasi. Itulah yang menyebabkan gerakan simbolik kultural tidak 13 selalu bersifat terbuka, dalam artian tidak selalu identik dengan adanya mobilisasi massa (Trijono, 2006). Berbeda dengan GSL yang dicirikan sebagai proses perjuangan kelas dan dalam banyak kasus diperjuangkan secara terbuka dengan mobilisasi massa. Karena gerakan simbolik kultural merupakan respon terhadap perubahan nilai, maka salah satu kelompok masyarakat yang mengambil peran dalam aktivitas gerakan adalah masyarakat adat. Menurut Selznick, sebagaimana dikutip Young & Minai (2002), masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok multifungsi yang berkaitan dengan kesejahteraan umumnya. Masyarakat dalam sekup kecil seperti keluarga hingga sekup besar seperti negara-bangsa adalah bagian dari komunitas, meskipun kedua ujung kontinum ini biasanya diperlakukan secara terpisah. Pada bagian ini, yang akan dibahas adalah komunitas adat (indigenous people). PBB melalui Indigenous Permanent Forum / IPF (2013), mencatat ada lebih dari 370 juta masyarakat adat yang tersebar di negara di seluruh dunia. Adapun hak-hak masyarakat adat menurut Executive Director of Cultural Survival, Ellen L. Lutz (2014) yaitu: pertama, masyarakat adat ingin menikmati dan mewariskan kepada anak-anak mereka mengenai sejarah, bahasa, tradisi, praktik spiritual, dan hal lain yang menjadi karakteristik mereka yang unik. Kedua, masyarakat adat ingin pemerintah di negara mereka menghormati kemampuan mereka utuk menentukan nasib sendiri. Mereka ingin mempertahankan lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan 14 budaya mereka – termasuk metode tradisional mereka dalam menyelesaikan sengketa internal, dan mengelola lingkungan mereka secara berkesinambungan. Ketiga, masyarakat adat ingin mendapatkan hak yang sama dengan semua orang, tanpa diskriminasi. Masyarakat adat ingin dilindungi dari genosida, relokasi paksa eksekusi sewenang-wenang, asimilasi, dan menikmati kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai dan norma yang mereka miliki. Keempat, masyarakat adat ingin menikmati hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional. Kelima, masyarakat ingin dibiarkan sendiri, dalam artiantanah leluhur mereka menjadi kepentingan mendasar bagi kelangsungan hidup kolektif dan budaya mereka sebagai masyarakat. Masyarakat adat memiliki konsep pembangunan yang beragam, berdasarkan tradisional nilai, visi, kebutuhan dan prioritas mereka. Artinya, setiap komunitas adat memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Dalam politik, suara masyarakat adat sering diabaikan dalam struktur sosial yang lebih tinggi. Hal itu terutama disebabkan oleh kurangnya keterwakilan dan partisipasi politik, kemiskinan dan marjinalisasi ekonomi, kurangnya akses pelayanan sosial; dan diskriminasi (IPF, 2013). Masalah umum itu juga terkait dengan perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, gerakan simbolik kutural yang dilakukan masyarakat adat pada dasarnya adalah untuk pengakuan identitas mereka, cara hidup mereka dan hak mereka atas tanah adat, wilayah dan sumber daya alam. 15 Menurut Jean Cohen (sebagaimana dikutip Kurniawan dan Puspitosari, 2012), GSB memiliki tujuan untuk menata kembali relasi antara negara, masyarakat, dan ekonomi. Demikian juga gerakan simbolik kultural yang cenderung ditujukan dalam rangka menciptakan kebebasan publik yang memadai terhadap wacana demokrasi. Adapun Alain Touraine (1981) yang menjelaskan gerakan simbolik kultural terkait dengan perubahan struktur dan kultur sebagai bentuk konflik pasca-industrial. Sebagaimana bentuk GSB pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam gerakan simbolik kultural adalah pendekatan refleksi untuk aksi yang menekankan transformasi sosial dan emansipasi (Trijono, 2006). Selain itu, Trijono (2006) juga menjelaskan enam fase berkembangnya GSB: mulai dari lahirnya kesadaran kritis; pengalaman praktis-historis; perbandingan dengan kelompok lain; transformasi menuju aksi; formulasi gerakan; dan aksi dalam arena gerakan. Terkait dengan itulah, keberhasilan GSB bergantung pada pentingnya jaringan, solidaritas kolektif, orientasi lokus hegemoni, hingga arena gerakan dalam kultural, pengetahuan praksis dan gerakan simbolik. Keenam fase sebuah gerakan simbolik kultural tersebut disederhanakan lagi oleh Trijono menjadi seperti berikut. 16 Transformasi Refleksi pengalaman praktis Formulasi agenda aksi Sumber: Trijono (2006) Adapun Hooghe (dalam Ishyama & Breuning (ed.), 2013) menulis gerakan sosial yang sukses tergantung pada kesempatan yang diciptakan atau ditawarkan oleh sistem politik negara bersangkutan. Digunakannya konsep gerakan simbolik kultural dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis gerakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Sengwer dalam merespon marginalisasi akibat penerapan program NRMP di Cherangany Hills, Kenya. 2.1.2 Konsep Marginalisasi akibat Pembangunan Marginalisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu diakibatkan oleh beberapa faktor; dari faktor ekonomi, sosial, budaya, yang keseluruhan berdimensi politik. Adapun marginalisasi yang ingin ditekankan dalam penelitian ini adalah marginalisasi yang disebabkan oleh program pembangunan modern. Lebih mengkerucut lagi, pembangunan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menganalisis persoalan lingkungan. Pendekatan strukturalis misalnya menempatkan aktor-aktor seperti negara, pengusaha, 17 hingga MNC memiliki kekuatan politik yang lebih kuat dalam mengatur pembangunan dan konservasi atau pemanfaatan lingkungan. Adapun pendekatan pascastrukturalis melihat persoalan ini lebih jauh lagi. Seperti yang pernah dilakukan Foryst (2007) yang menemukan ternyata kasus di dunia ketiga tidak hanya degradasi lingkungan, tetapi juga marginalisasi masyarakat lokal, justru karena program konservasi lingkungan tersebut. Harrison (1988) membagi marginalisasi yang diakibatkan oleh pembangunan menjadi dua; yaitu marginalisasi secara struktural dan kultural. Secara struktural, pemerintahan domestik dalam sebuah negara telah menjadi agen untuk menciptakan pasar kapitalis melalui program-program pembangunan. Di sini, pemerintah (negara) dapat menggunakan perangkat atau aparatus pendukungnya serta melalui kebijakan-kebijakan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah bahkan didukung oleh kekuatan supranasional yang memiliki kepentingankepentingan tertentu; seperti sistem kapitalisme global. Hal ini menunjukkan relasi kuasa nasional (negara) dan supranasional (sistem kapitalisme global) akan membawa kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi termarginalisasi. Sedangkan secara kultural, masyarakat telah dihegemoni oleh konsep-konsep pembangunan yang materialistik dengan menjanjikan modernisasi dan kesejahteraan ekonomi. Jean Pierre dan Oliver de Sardan (2005) melihat perubahan sosial telah menunjukkan adanya pertentangan berbagai logika sosial yang membayangi 18 program-program pembangunan. Dampaknya, budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat yang menjadi objek pembangunan, terpaksa menerapkan sesuatu yang bukan menjadi nilai mereka. Inilah awal dari munculnya marginalisasi akibat pembangunan, yaitu masyarakat lokal telah kehilangan pandangan partikularitasnya. Dikaitkan dengan sistem global, modernisasi pembangunan telah mempertentangkan wacana universal (melalui program-program pembangunan global) dengan wacana partikular (nilai-nilai lokal yang menyangkut identitas dan simbol-simbol kultural tertentu). 2.1.3 Konsep Konservasi Alam berbasis Developmentalisme Menurut D‟Andrea (2013), sejak peresmian Taman Nasional Yellow Stone di Amerika Serikat pada tahun 1873, ilmu konservasi modern terus berkembang. Konservasi modern secara umum memiliki paradigma bahwa tujuan konservasi adalah menyediakan suatu bentang alam yang digunakan untuk melestarikan hewan-hewan dan atau tumbuhan dan atau ekosistem yang rentan dan dianggap akan punah. Tahun 1990-an, terbentuk lembaga supranasional yang dirancang untuk mengatur investasi lingkungan secara internasional dan arus lintas batas sumber daya alam, termasuk pengetahuan tentang alam dan informasi genetik (McAfee, 1999). Perkembangan ilmu konservasi tersebut diiringi dengan perjanjian-perjanjian internasional mengenai lingkungan, seperti Framework Convention on Climate, Change 19 and the Convention on Biological Diversity (CBD), dan the Global Environment Facility. Perubahan paradigma koservasi modern disertai juga dengan penggunaan pengetahuan modern dengan teknik-teknik modern pula. Sehingga, metode konservasi tradisional dianggap tidak ilmiah, dan karena itu mulai banyak ditinggalkan. Selain itu, konservasi modern ini menjanjikan masalah lingkungan dapat dijamin melalui solusi pasar dengan paradigma eco-ekonomi. Pendekatan yang demikian menunjukkan konservasi alam yang berbasis developmentalisme (McAfee, 1999). Dalam bukunya berjudul Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Fakih (2011), menjelaskan teori pembangunan dengan pendekatan kritis. Fakih menolak anggapan umum yang mengatakan pembangunan adalah kata benda netral yang hanya menekankan proses dan usaha meningkatkan kehidupan ekonomi, poitik, budaya, infrastruktur masyarkat, dan sebagainya. Definisi pembangunan yang demikan, menurut Fakih, telah mendominasi pandangan mengenai diskursus perubahan sosial. Fakih kemudian memperkenalkan pandangan yang lebih minoritas mengenai asumsi „pembangunan‟. Dari perspektif ini, pembangunan dipandang sebagai “sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial” (hal. 10). Paham developmentalisme juga sering dikaitkan dengan modernisme. Modernisme yang lahir sebagai respon kaum intelektual 20 terhadap Perang Dingin sejak 1950-an dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Fakih (2012), teori modernisme dikembangkan terutama untuk menjadi jawaban pada permasalahan di Dunia Ketiga dalam usaha membendung sosialisme dan mendorong kapitalisme. Dalam The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Rostow (2012) menjelaskan faktor manusia merupakan yang paling berpengaruh terhadap kemajuan peradaban manusia – bukan karena struktur atau sistem. Untuk menjelaskan kemajuan peradaban manusia itu, Rostow berasumsi bahwa masyarakat pada mulanya pernah mengalami masa tradisional dan kemudian menjadi modern. Tujuan utama modernisasi adalah mendorong masyarakat yang berbasis pada industrialisasi dan ditandai dengan masyarakat konsumsi tinggi. Dengan demikian, modernisasi pun bukan merupakan kata yang netral, melainkan juga telah menjadi sebuah aliran – dan karenanya, sering digunakan secara bergantin dengan kata pembangunan atau developmentalisme. Karena develomentalisme diartikan sebagai satu-satunya cara untuk menuju perubahan sosial yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui modernisasi, kritik terhadapnya pun lebih banyak datang dari golongan tradisionl. Fakih (2012) menulis kritik dari golongan tradisional berangkat dari paham developmentalisme yang menganggap data atau model tradisional kurang valid. Menurut kritik ini, developmentalisme bahkan telah 21 menjadi propaganda untuk menciptakan hegemoni pengetahuan. Inilah yang banyak dihadapi negara Dunia Ketiga, dimana pengetahuan tradisional dan kearifannya berhadapan dengan pengetahuan modern yang berangkat dari model pembangunan Barat. Dengan demikian, pendekatan konservasi berbasis develompentalisme mencerminkan upaya aktor kapitalis untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan, misalnya, oleh iklim yang tidak stabil. Artinya, konservasi berbasis developmentalisme mencoba merasionalisasi praktik industri dan perhitungan biaya kerusakan ekologis, tanpa mengurangi keuntungan. Pendukung dari metode ini menyerukan berbagai dana, keringanan pajak, dan insentif lainnya dengan cara mensubsidi negaranegara, memperkenalkan program-program pembangunan global, dan teknologi hijau (McAfee, 1999). 2.1.4 Teori Ekologi Politik di Negara Berkembang Menurut Bryant & Bailey (1997), tujuan utama penelitian ekologi politik di negara berkembang adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kesejahteraan ekonomi, proses politik, dan degradasi lingkungan. Bila politik menekankan pada bagaimana kekuasaan dikejar, maka aktivitas ekonomi erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan. Bryant & Bailey (1997) kemudian menegaskan degradasi 22 lingkungan terjadi bukan karena faktor alami, melainkan menyangkut aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik yang dilakukan manusia. Perkembangan isu ini mulai mendapat perhatian sejak tahun 1970-an yang ditandai dengan munculnya studi ekologi politik (Bryant & Bailey, 1997). Menurut Piers Blaikie, sebagaimana diulas Foryst (2007), studi ekologi politik tidak mau memisahkan diri antara politik atau ekologi, atau hanya melihat salah satu sebagai sebuah petunjuk. Justru, ekologi politik melihat keduanya sebagai kesatuan yang diharapkan akan menciptakan keadilan sosial. Diehl & Gleditsch (2001) juga menjelaskan hal yang sama. Menurut mereka, memang terdapat perdebatan tentang politik dan ekologi yang mencoba mengabaikan bagaimana keduanya terkait. Namun, sebagian besar para akademisi juga sepakat bahwa ekologi politik mencatat bagaimana ilmu lingkungan kritis dan politik struktural menimbulkan narasi lingkungan dan keyakinan yang sederhana –dan sering membantu orang-orang miskin. Ekologi politik tidak harus mengadopsi pemahaman yang terpisah dari politik atau ekologi, atau melihat satu sebagai panduan untuk yang lain. Justru, menurut Diehl & Gleditsch (2001), tantangan ekologi politik terletak pada pemahaman akan politik dan perubahan lingkungan dengan tujuan meningkatkan keadilan sosial, tetapi tidak memaksakan gagasan apriori tentang masing-masing. 23 Di negara-negara berkembang, isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya tidak terlalu mendapat perhatian oleh partai-partai politik. Oleh karena itu, para pemikir ekologi yang pada mulanya memfokuskan ekologi manusia, kemudian mengembangkan arah kajiannya menjadi politik ekologi. Dharmawan (2007) menjelaskan ekologi politik terkait dengan ruang konflik dan ruang kekuasaan. Ruang konflik menyangkut proses artikulasi berbagai kepentingan yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan politik. Sedangkan, ruang kekuasaan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan politik oleh para pemegang otoritas kebijakan. Kedua ruang inilah yang mendasari kondisi lingkungan erat kaitannya dengan produk proses-proses dialektik ekonomi dan politik. Bryant & Bailey (1997) menjelaskan, di negara berkembang kerusakan lingkungan berkaitan dengan tiga hal. Pertama, terdapat marginalisasi kelompok-kelompok sosial tertentu, biasanya komunitaskomunitas yang mendiami suatu ruang tertentu. Kedua, kondisi sosial ekonomi akan rentan karena berlangsungnya kerusakan yang terus menerus. Ketiga, muncul resiko kehancuran taraf lanjut bagi kehidupan masyarakat di lingkungan yang mengalami kerusakan. Ketiga hal itu kemudian yang menjadi alasan pentingnya melakukan perjuangan politik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kajian ekologi politik, perjuangan politik itu juga bertujuan untuk membongkar relasi kuasa yang berpengaruh terhadap pemecahan permasalahan lingkungan, terutama di negara dunia ketiga.