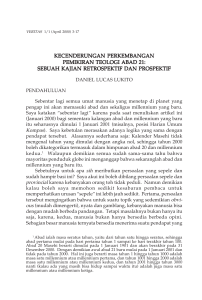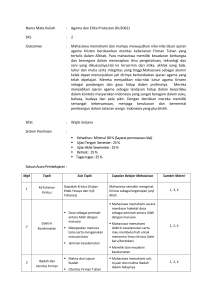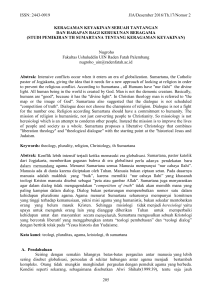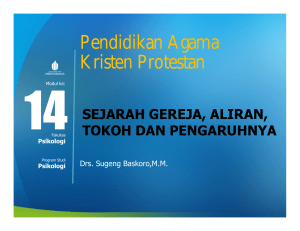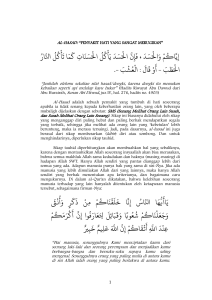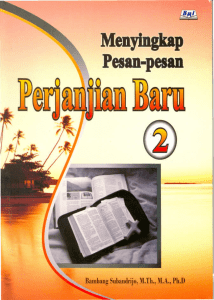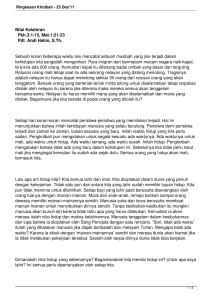RELATIVISME, PLURALISME, DAN PERGULATAN BUDAYA [Pdf.]
advertisement
![RELATIVISME, PLURALISME, DAN PERGULATAN BUDAYA [Pdf.]](http://s1.studylibid.com/store/data/000073733_1-3c7a9996da0f7e7d7dec4f26cf3fe9f5-768x994.png)
1 RELATIVISME, PLURALISME, DAN PERGULATAN BUDAYA1 Armada Riyanto CM 1. RELATIVISME Pernyataan tentang relativisme pertama kali muncul dari filosof sophis, Protagoras (490420 BC) lima ratus tahun sebelum Masehi. Pernyataan Protagoras dikutip oleh Plato: “The way things appear to me, in that way they exist for me; and the way things appears to you, in that way they exist for you”(Theaetetus 152a). Maksud kata-kata Protagoras demikian: sesuatu nampak di hadapanku dalam caranya yang khas, dan dalam cara yang khas itu pula sesuatu ada untukku; demikian juga apabila kamu berhadapan dengan sesuatu, sesuatu itu secara khas ada untukmu. Kalimat Protagoras ini mengandaikan satu dua prinsip sederhana untuk mengertinya. Yaitu, prinsip yang pertama, setiap pengetahuan atau pengenalan (knowledge) selalu merupakan pengetahuan atau pengenalan akan sesuatu (thing). Prinsip kedua, setiap pengetahuan berasal dari pengamatan inderawi (as it appears to me). Pengetahuan saya mengenai langit, i.e., bahwa langit itu biru, memiliki introduksi instrumen inderawi saya (mata) yang menangkap penampakan langit sebagai demikian. Tetapi, harus diakui, ketika mata orang lain melihat langit berwarna putih abu-abu (as it appears to him/her), ia akan berkata bahwa langit tidak biru, melainkan abu-abu. Tampaknya pemahaman filosof Protagoras ini sederhana. Tetapi, halnya akan menjadi masalah serius ketika berkaitan dengan ranah persoalan yang lebih luas. Mari kita memahami sedikit lebih dalam pernyataan Protagoras ini. Karena langit (thing) bisa biru atau abu-abu atau putih atau hitam atau juga tidak berwarna sekalipun, maka apa pun yang kita maksudkan untuk menjelaskan pengetahuan kita mengenai warna langit selalu benar tergantung dari mata yang menangkapnya. Konsekuensi runyamnya, tidak ada pengetahuan salah. Atau, malahan tidak ada pengetahuan apa-apa tentang langit. Ya … tidak ada pengetahuan salah, sebab apa pun yang kita katakan mengenai sesuatu (thing) memiliki relasi dengan indera yang menangkapnya (as it appears). 1 Artikel ini saya kerjakan tahun 2010. Beberapa bagian tema dari tulisan ini telah muncul dan dikembangkan dalam buku Dialog Interreligius. Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah (Kanisius, 2010) dan buku Katolisitas Dialogal. Ajaran Sosial Katolik (Kanisius, 2014). Beberapa tema mengalami revisi atau perluasan dalam pembahasannya di kedua buku tersebut. Para pembaca, tentu saja, saya harapkan lebih merujuk ke kedua buku tersebut untuk akurasi argumentasi dan uraiannya. 2 Inilah asal muasal relativisme. Istilah “relativisme” diambilkan dari bahasa Latin, relativus, yang artinya “menunjuk ke.” Setiap pengetahuan, menurut paham relativisme, selalu memiliki rujukan, referensi. Dengan demikian, setiap pengetahuan memiliki logika dan ranah kebenarannya sendiri bergantung kepada rujukannya. Relativisme meniadakan kebenaran universal. Jika tidak ada pengetahuan yang salah, karena setiap pengetahuan memiliki rujukannya sendiri, maka juga tidak ada pengetahuan yang benar secara universal. Jika tidak ada pengetahuan yang benar secara universal, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada pembelajaran, tidak perlu ada diskusi hukum-hukum, tidak perlu ada komunikasi (malahan). Sebab, semuanya benar belaka. Inilah konsekuensi paling telak dari relativisme protagorasian. Kita tahu bahwa dalam hidup sehari-hari komunikasi berarti aktivitas mengkomunikasikan kebenaran. Kebenaran memiliki karakter komunikatif, performatif, promotif. Kebenaran itu komunikatif, itu sebabnya kita selalu haus dan rindu akan kebenaran. Kebenaran itu performatif, sebab kebenaran itu menampilkan diri, tidak menyembunyikan diri. Kebenaran itu promotif, karena itu kebenaran tidak bisa dibuntu, tidak bisa dicegah. Kebenaran itu malahan memikat, memukau, menarik kita untuk memeluknya. Relativisme itu tidak plausible, menurut filosof Sokrates dan Plato, sebab meniadakan kodrat indah dari kebenaran itu sendiri. Jika pengetahuan apa saja dalam metodologi bagaimana pun selalu benar, seperti yang dideklarasikan oleh Protagoras, kita tidak pernah tertarik akan kebenaran pengetahuan itu sendiri. Sejak dikenalkan terminologi “subjek” dan “objek”, relativisme diidentikkan dengan subjektivisme. Artinya, pengetahuan relatif adalah pengetahuan yang bergantung atau memiliki referensi (atau related to) subjek-nya. Dalam filsafat ilmu pengetahuan (atau epistemologi), pengetahuan sesungguhnya merupakan relasi subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Contoh, dalam pengetahuan “langit itu biru”, produk kebenaran “biru” adalah hasil dari relasi aku sebagai subjek yang mengetahui dengan langit sebagai objek yang saya ketahui. Jalan pikiran ini ada benarnya, ketika kita mengingat bahwa pengetahuan “Tuhan itu murah hati” (misalnya) berasal dari pengalaman saya yang mengalami dalam cara yang khas bahwa Tuhan adalah demikian. Kemurahan hati Tuhan tidak bisa diberitahukan, tidak dapat sekedar sebagai sebuah informasi, melainkan harus menjadi sebuah pengalaman. Sejak Yohanes Paulus II Gereja Katolik didesak untuk memanfaatkan sebaik mungkin kemajuan teknologi komunikasi yang secara hebat merambah hidup manusia. Baru-baru ini Paus Benediktus XVI juga mengobarkan semangat yang sama untuk memanfaatkan sarana teknologi komunikasi untuk katekese dan aneka tugas pewartaan. Tak ayal lagi, Facebook dan Twitter adalah web-web yang paling sering dibuka. Tidak hanya kaum muda (dari sendirinya), melainkan juga religius, imam, dan para uskup. Asal diperhatikan, komunikasi virtual lewat media internet jangan sampai meniadakan relasi personal, pelayanan kehadiran, sapaan konkret, dan realisasi pembaharuan paguyuban secara nyata dalam hidup sehari-hari. Artinya, ranah iman adalah ranah pengalaman keseharian. 1.1.Relativisme Etika 3 Relativisme protagorasian paling terkenal dalam ranah etika. Relativisme etis berarti segala apa yang kita maksudkan nilai baik selalu memiliki rujukan. Baik itu relatif, berkaitan dengan referensi dan relasinya dengan sudut pandang konteksnya. Baru-baru ini saya melakukan perjalanan tugas bersama para rektor APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta) ke Cina. Di dalam bus yang nyaman, guide yang ramah selalu menemani kami dengan banyak informasi tentang negeri Cina yang mengalami kemajuan pesat. Dari banyak kemajuan, pemandu wisata bercerita juga tentang ledakan penduduk dan kesulitan serius yang dihadapi Cina. Ia berkata demikian: “Di sini keluarga dibatasi untuk punya anak hanya satu. Pembatasannya secara konkret direalisasikan dalam hukum yang tegas. Maka, jika di Hongkong aborsi diancam sanksi hukum, di sini banyak orang kalau tidak melakukan aborsi, setelah anak pertama lahir, justru akan dikenai sanksi hukuman tidak ringan.” Kisah tentang aborsi ini menarik untuk disimak. Jelas bahwa aborsi sebagai tindakan mematikan manusia (janin) merupakan tindakan yang melanggar moral. Tetapi, dalam ranah konteks Cina, aborsi nampak mengalami pergeseran penilaian moral. Sekurang-kurangnya itu yang saya dengar dari guide kami. Uniknya, ketika saya bertanya kepada rekan-rekan rektor, halnya seperti tidak menjadi isu penting untuk dibahas dan diprihatini. Relativisme etis memiliki banyak sebutan dan nama, seperti etika kontekstual, etika utilitarian, dan sejenisnya. Etika kontekstual berarti nilai baik buruk dipondasikan pada rujukan konteksnya. Dalam konteks Keluarga Berencana karena suatu problem ledakan penduduk yang hebat, seakan-akan aborsi dipandang sebagai sebuah pemecahan baik. Sedangkan etika utilitarian merujuk kepada statement Machiavelli bahwa apabila seorang penguasa perlu melakukan sebuah tindakan keburukan untuk kebaikan yang lebih besar, hendaknya tidak perlu merasa bersalah. Konteks pemikiran Machiavelli adalah sebuah tujuan yang baik dapat diraih dengan cara apa pun, termasuk cara-cara yang buruk. Greatest happiness for greater number adalah konsep etika utilitarian. Persoalannya, jika kesejahteraan dimaksudkan untuk kelompok masyarakat yang lebih besar, bagaimana dengan kelompok minoritas. Jika kebenaran direduksi pada kepentingan umum yang lebih besar, kepentingan kelompok minoritas dari sendirinya dapat dengan mudah ditindas. Bentuk dari nilai baik, menurut filosof Epicuros (341-270 SM), mewujud dalam pleasure, kenikmatan. Maksudnya, kenikmatan yang mengalir dari makan dan minum. “The root of all good is the pleasure that comes from eating and drinking”. Gagasan “kenikmatan” dalam Epicurianisme memaksudkan arti yang sangat mendalam. Kenikmatan memang menjadi sangat jelas dan konkret dalam aktivitas makan dan minum. Tetapi, ide kenikmatan menyentuh pada soal bahwa aktivitas kehidupan manusia haruslah terarah kepada segala apa yang berkaitan untuk menghindari kesengsaraan, penderitaan, kecemasan, dan seterusnya. Para epicurian adalah para pemuja kehidupan, lebih dari sekedar penyanjung kenikmatan atau kepuasan fisik yang rendah. Pleasure Epicurian diteruskan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832). Menurut Bentham, man necessarily seeks to have as much pleasure as he can and to avoid pain at all costs. “Nature has placed humankind under the government of two sovereign masters: pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand, the standard of right or wrong, on the other, the chain of causes and 4 effects, are fastened to their throne. They (pain and pleasure) govern us in all we do, in all we think ...” (Bentham, Jeremy. The Principles of Morals and Legislation (1789) Ch I, p. 1) Bentham memandang dengan sangat jelas bahwa kehidupan manusia diatur dan ditata sedemikian rupa melulu pada pendasaran untuk menghindari derita dan mengejar kenikmatan. Pain and pleasure sedemikian kuatnya sehingga orang tidak bisa menghindarkan diri dari hegemoni/kekuasaan dua instansi ini (pain and pleasure). Segala pertimbangan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada pain and pleasure. Jeremy Bentham ini nantinya akan menginspirasikan etika utilitarian John Stuart Mill. Etika utilitarian berarti segala penilaian baik buruk atas tindakan manusia didasarkan semata-mata pada soal berguna atau tidak berguna. 1.2. Relativisme dan Krisis Nilai Seringkali disimpulkan bahwa dewasa ini relativisme telah menyebabkan krisis nilai. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam krisis nilai? Krisis nilai kerap kali dikaitkan dengan merosotnya nilai-nilai moral kehidupan. Apa artinya nilai moral mengalami kemerosotan? Fenomen tindakan korupsi dipandang wajar. Kekerasan terhadap manusia, main hakim sendiri, perkosaan, pemukulan (guru terhadap anak didik / juga anak didik terhadap gurunya), perampokan, pembacokan, dan teror merebak di mana-mana. Tambahan lagi, praktek aborsi ilegal di mana-mana menjadikan tindakan “membunuh janin” serentak seakan-akan menjadi jalan wajar untuk memecahkan masalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Di dalam fenomenfenomen ini, yang terjadi sebenarnya bukan nilai-nilai mengalami proses relatifnya, melainkan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri langsung tidak mendapat penghormatan yang secukupnya. Manusia mengalami proses pendangkalan dalam menghayati kehidupannya, kehidupan sesamanya, dan kehidupan bersamanya dengan orang lain. Krisis nilai dengan demikian tidak sama sekedar sebagai suatu krisis konsep atau gagasan atau ide mengenai kebaikan. Krisis nilai adalah krisis kehidupan dalam artian etis dan moral secara mendalam, real, konkret. Krisis nilai dalam artian filosofis terjadi sejak Nietzsche, karena dia memproklamasikan kematian Allah. Kematian Allah berarti lenyapnya segala pendasaran moral/etika/nilai. Nilai kehilangan pondasi terakhirnya. Karena Allah “dibunuh”, nilai menjadi kalang kabut. Bukan hanya agama yang ditindas, tetapi juga kehidupan lantas kehilangan kepastiannya. Di sini tidak dimaksudkan seakan-akan Allah mati seperti manusia mati. Maksudnya, Nietzsche dengan proklamasinya mengenai kematian Allah telah merobohkan pondasi paling akhir dari moralitas/etika manusia. Mengenai dasar-dasar etis/moral lantas harus dicari dari dalam diri manusia itu sendiri. Bagaimana melegitimasi eksistensi nilai moral di hadapan Nietzsche? Argumentasi apa yang hendak kita katakan pada Nietzsche? Penolakan moral dalam kehidupan nyata oleh Nietzsche mendapat tanggapan hebat dari kalangan filosof fenomenologis yang mengajukan kesadaran-kesadaran baru mengenai nilai moral. Bahwa dalam menyimak fenomen-fenomen kehidupan kiranya naif jika tidak mengakui realitas nilai. Dapatkah kita membutakan diri terhadap aneka kekerasan dan ketidakadilan yang nyata dalam masyarakat dan memandangnya melulu sebagai peristiwa tanpa nilai. 5 Sebutlah misalnya (ini peristiwa masa lampau) seorang pengemudi becak yang terpaksa menggantung diri karena ada peraturan baru dilarang membecak di kota Jakarta, padahal becak baru satu minggu yang lalu dibeli dengan kredit yang berbunga 50% per bulan. Dapatkah kita berkata bahwa itu hanya sebuah peristiwa tanpa ada nilai-nilai yang menyertai dan berpartisipasi dalam peristiwa itu? Atau, seorang nenek renta yang mencari makan untuk menyambung hidupnya dengan mencuri daun pisang di tanah milik tetangga dibunuh oleh sang pemilik tanah karena kesal dan jengkel terhadap perbuatan mencuri dari si nenek. Dapatkah kita melihat peristiwa kematian ngenas dari sang nenek renta tersebut hanya sebagai suatu fenomen biasa tanpa nilai, misalnya nilai keadilan yang dirampas oleh sang pemilik tanah dari hidup sang nenek? Atau, Salah satu bukti krisis nilai di Indonesia ialah apa yang saya ingin sebut sebagai formalisme. Formalisme di Indonesia (dan ini mengatakan sebuah krisis) bermula dari aneka perkara artifisial (perkara-perkara politis yang seolah-olah dibuat-buat saja). Simak bagaimana perkara Bibit-Chandra telah mendominasi headlines seluruh surat kabar Indonesia. Dan, ternyata itu tidak ada apa-apa. Sebuah rekayasa belaka. Ternyata “cicak sedang berhadapan dengan buaya” saja. Perkara hukum Luna Maya yang mencela para wartawan infortainment, dan kita semua dibuat terbengong-bengong. Ternyata, tidak ada apa-apa. Itu dua tiga kata dalam Twiter yang menjadi ungkapan kegatalan dan kejengkelan si Luna. Formalisme membuat tata hidup bersama berada dalam tataran yang paling rendah. What is at stake (apa yang dipertaruhkan) dalam formalisme? Lenyapnya kepastian. Tidak ada lagi makna kepastian kebenaran dalam keseharian di satu pihak dan kita seakan malah disergap oleh krudelitas (kekejaman) sistem keadilan yang absurd dan nyleneh. Pritasari beberapa waktu yang lalu (yang bergumul dengan pengadilan absurd karena sebuah email keluhan), Minah (yang mengucapkan elegi di pengadilan atas pencurian tiga kakao), kesepuluh anak SD Tangerang (yang diseret ke meja hijau lantara bermain “judijudian”), Suyanto dan Kholil (yang dituntut dua bulan penjara karena dua buah semangka), Parto (yang diancam lima tahun bui karena memangkas lima batang pohon jagung untuk tambahan makan kambingnya), Sarjo 77 tahun (yang dipenjarakan atas perkara dua batang sabun dan sebungkus kacang seharga Rp. 13.450), mereka semua adalah emblem keseharian hidup kita yang sarat ketidakpastian. Dan, masih banyak lagi kawan-kawan mereka yang senasib ditelan krudelitas (kejamnya) dan absurditas (“kenylenehan”) tata hukum negeri ini. Sementara itu, para mafiosi peradilan, para makelar kasus, para penegak hukum yang korup, para koruptor dan yang sejenisnya tidak bisa ditahan karena kekurangan bukti perkaranya. Keseharian identik dengan ketidakpastian, sebab peradilan telah berubah menjadi sebuah selebrasi (perayaan) yang elegan tetapi rentan kepalsuan. Keseharian adalah kecemasan, sebab yang kecil-miskin menjadi tokoh-tokoh pelengkap penderita sandiwara sinetron kehidupan yang tak bermutu. Keseharian adalah keputusasaan, sebab Minah-Suyanto-Kholil-Parto-Sarjokesepuluh-anak-Tangerang tidak bisa mengucapkan pledoi sama sekali melainkan elegi. Elegi mereka seakan menjadi eulogi keadilan negeri ini. Elegi adalah puisi ratapan. Eulogi memaksudkan kata-kata yang diucapkan untuk mengiringi penguburan. Tata keadilan hidup seakan telah berada di liang penguburan. 6 Formalisme telah seakan membuat kehidupan keseharian yang cerah menjadi redup oleh mendung keangkuhan hukum di satu pihak dan ketidakpastian tentang keadilan di lain pihak (simak juga bagaimana seorang suami yang kehilangan isterinya telah justru dipenjarakan dengan aneka tuduhan yang menjadi milik hukum tetapi absurd dari perspektif sehari-hari.) Pertimbangan moral sebagai demikian diberikan oleh kesadaran manusia. Manusia sejauh memiliki kesadaran dalam tindakannya, dia selalu mengajukan nilai-nilai. Jadi diskusi mengenai nilai moral harus langsung diandaikan sejauh manusia ada, hidup, bertindak. Kesadaran dan kehidupan manusia adalah bukti yang secara fenomenal mengatakan tampilnya nilai-nilai. Mengenai benarnya eksistensi nilai sejauh manusia sadar, kita barangkali bisa membandingkannya dengan revolusi filsafat Descartes. Jika dalam Descartes cogito ergo sum (saya berpikir/sadar maka saya ada), dalam etika cogito (saya berpikir/sadar) maka saya mengajukan nilai-nilai. Fenomen nilai muncul dari aktivitas penilaian kita terhadap orang lain/diri sendiri. Aktivitas penilaian ini menjadi ciri khas manusia. Kesadaran paling langsung dan serentak mengenai nilai jelas dalam kenyataan bahwa kita “menilai” diri sendiri dan orang lain. “Menilai” diri sendiri artinya kita melakukan paling sedikit kesadaran akan segala apa yang kita lakukan, rasakan, pikirkan, olah dan seterusnya. Kesadaran semacam ini jelas memproduksi nilai-nilai atau sangat mengandaikan paham-paham nilai-nilai. Bisakah dibayangkan orang menilai dirinya sendiri atau orang lain sekaligus menyangkal adanya nilai-nilai? Dalam kenyataan bahkan harus dikatakan bahwa suatu penilaian hanya mungkin apabila ada semacam paradigma tertentu mengenai nilai sebagai demikian. Fenomen kewajiban dan nilai moral. Nilai moral bukan optional, melainkan wajib. Di hadapan nilai, kita tidak mungkin bersikap ya atau tidak. Nilai moral adalah fenomen kewajiban. Kesaksian tentang kewajiban ada dalam tindakan dan bahasa manusia sehari-hari. Kewajiban manusia hadir dalam tindakan dan bahasa, bukan pikiran. Bahasa melukiskan, mengungkapkan, memberikan wacana (referensi) atau yang semacamnya berkaitan dengan fenomen kewajiban. Tindakan mewujudkan kewajibannya. Dengan demikian, konfirmasi mengenai karakter normatif etika ada dalam keseharian hidup manusia. Karakter normatif etika dibuktikan dalam fenomen peristiwa-peristiwa kehidupan konkret. Prinsip bonum faciendum & malum vitandum (kebaikan harus dilakukan dan keburukan harus dihindarkan) adalah penegasan realitas bahwa hidup manusia langsung menyentuh kewajiban moral. Mengapa kebaikan harus atau wajib dilakukan dan keburukan harus atau wajib dicegah? “Harus” artinya wajib, mutlak, tidak boleh tidak, punya daya ikat. Mengapa Baik itu punya daya ikat untuk dilakukan? Bagi Kant, karena itulah kodrat kebaikan. Kodrat Baik itu sekaligus mencetuskan “harus”. Bagi Aristoteles, kebaikan harus dilakukan karena menjanjikan kebahagiaan. Etika kebaikan Aristotelian bersifat teleologis, yaitu menuju kepada kebahagiaan. Dengan demikian, kebahagiaan jelas merupakan itu yang tidak datang dari sendirinya, tidak begitu saja diraih. Kebahagiaan adalah itu yang harus dikejar, diperjuangkan, diraih. Jika dalam Aristoteles, keharusan untuk menjalankan kebaikan menemukan alasannya pada tujuan kebahagiaan, dalam Kant keharusannya ada pada kodrat kebaikan itu sendiri. Bagi filsafat fenomenologi, kebaikan adalah fenomen yang memikat, mempesona, menarik untuk dikejar, diraih. 1.3.Relativisme dalam Teologi 7 Dewasa ini relativisme merambah pula wilayah teologi. Relativisme teologis kerap bergandengan dengan indiferentisme. Indiferentisme adalah sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran iman. Indiferentisme mengalir dalam pola-pola tata hidup beriman yang tidak terarah. Segala yang merupakan imperatif hidup iman dipandang tidak penting. Para penganut paham relativisme dalam teologi memandang bahwa eksklusivisme adalah sumber dari kekerasan bertajuk agama. Dari pengalaman pertemuan dengan agama-agama (dan budaya) lain di masa lampau, sikap agama Kristen mula-mula tercetus dalam sikap eksklusif. Agama-agama lain dipandang mengancam keberadaan agama Kristen. Aneka pandangan dan ajaran yang mengalir dari tradisi religius agama lain atau ajaran lain dianggap mengacau dan membahayakan keotentikan iman Kristen.2 Dari sebab itu Gereja pertama-tama cenderung mengambil sikap mengalahkan, menundukkan agama-agama lain dan membela kebenaran sendiri. Eksklusivisme agama Kristen di masa lampau muncul berbarengan dengan perjuangan pertama Gereja untuk menegaskan eksistensinya sebagai yang memiliki kebenaran satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan. Menurut Lucient Richard (1981), eksklusivisme agama Kristen Awali berakar pada pemahaman Gereja terhadap ajaran Perjanjian Baru yang menekankan keunikkan Kristus dan menegaskan finalitas sejarah keselamatan dalam diri Kristus.3 Dalam Perjanjian Baru Kristus menjadi pusat pewartaan. Penekanan atas keunikan dan finalitas Kristus dilandaskan pada konsep Perjanjian Baru mengenai Inkarnasi dan eskatologi. Inkarnasi melukiskan "Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama daripada segala sesuatu" (Kol 1:15). Dan eskatologi menyatakan bagaimana pemenuhan sejarah keselamatan manusia telah terwujud di dalam manusia Kristus. Menurut Richard, pemahaman ini merupakan pemutlakan sekaligus pembekuan sejarah (keselamatan) manusia pada satu manusia dan pada satu saat sejarah saja.4 Dan dengan demikian juga merupakan pemutlakan kebenaran iman Kristen. Tetapi, di luar ranah dogmatik, ungkapan eksklusivisme paling jelas tampak dalam adagium extra ecclesiam nulla salus. Walaupun ungkapan ini pada awal kemunculannya bersifat apologetis (untuk membela ajaran kebenaran iman), tetapi kemudian tumpang tindih dengan peradaban ideologis kekuasaan Barat atas wilayah-wilayah yang baru ditemukan merupakan realitas yang tak terelakkan. Adagium ini pertama kali berasal dari Santo Cyprianus (abad 3), di mana pada waktu itu konsep tentang agama-agama di luar Kekristenan tidak atau belum ada. Dengan ungkapan itu Cyprianus hendak mengatakan perihal baptisan yang diberikan oleh para bidaah (yang mengucilkan diri dari Gereja yang benar) sebagai salah dan tidak membawa kepada keselamatan. Pandangan Cyprianus (dan kemudian juga para Bapa Gereja yang lain, seperti Irenaeus, Clemens dari Alexandria, dan Origenes) bertolak dari pemikiran bahwa Gereja merupakan "bahtera" Nuh yang menyelamatkan para penghuni di dalamnya. Yang memisahkan diri dari sendirinya juga menjauhkan diri dari keselamatan itu sendiri. Santo Agustinus juga mengatakan yang serupa 2 Gerard Valee, A Study in Anti Gnostic Polemics (Waterloo, Can: Wilfrid Laurier University Press, 1981), hal. 99. Kutipan diambil dari Harold Coward, Pluralism. Challenge to World Religions (New York: Orbis Books, 1985), hal. 20. 3 Lucient Richard, What Are They Saying about Christ and World Religions? (New York: Paulist Press, 1981), hal. 6-7. Lihat Ibid., hal. 17. 4 Lihat juga Stanislaw Celestyn Napiorkowski, "'Christus Solus Nunquam Solus': Toward Reinterpretation of the Principle 'Solus Christus'", dalam Journal of Ecumenical Studies, 20:1, Winter 1983, hal. 454-476. 8 bahwa di luar Gereja Katolik ada apa saja, kecuali keselamatan. Ungkapan itu sesungguhnya hanyalah "pagar" untuk mencegah di satu pihak keluarnya umat Kristen dari ajaran yang benar tentang iman Kristen, dan di lain pihak ingin meyakinkan kesesatan padangan-pandangan para bidaah dan kaum gnostis. Tetapi salah tafsir mengenai adagium itu tak terelakkan lebih-lebih di abad kolonialisme. Penafsiran berubah makin meluas, yakni di luar iman kepada Kristus atau bahkan di luar Gereja (Katolik), tidak ada keselamatan. Tentu saja akibatnya Gereja terkurung dalam eksklusivisme. Menurut Harold Coward, pemutlakan iman Kristen bagi keselamatan menemukan bentuk sistematisasi teologisnya pada pandangan Karl Barth (1961)5, seorang teolog Protestan terkemuka abad ini. Pandangan Barth dapat dikatakan menjadi wakil bentuk baru eksklusivisme teologi Kristen dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Barth bertolak dari pandangan bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan wahyu Allah. Dalam diri Kristus, penyataan diri Allah kepada manusia menjadi konkret, final, dan definitif. Karena itu satu-satunya perbedaan agama Kristen dan agama-agama lain ialah bahwa agama Kristen berdiri di tempat terang, sementara agama-agama lain dalam bayang-bayang. Barth menganalogikan Kristus bagai matahari yang menerpa bumi, satu bagian terkena (agama Kristen) dan bagian yang lain ada dalam bayang-bayang (agama-agama lain). Barth menegaskan pandangannya dengan mengadakan penilaian teologis atas umat manusia sebagai subjek semua agama. "Bagi manusialah, entah dia mengetahui atau tidak, Yesus Kristus lahir, wafat, dan bangkit kembali. Bagi manusialah, entah dia mendengarnya atau tidak, Firman Allah diperuntukkan. Dan manusialah, entah dia menyadari atau tidak, yang menemukan Allahnya dalam Kristus." Yang hendak ditegaskan Karl Barth ialah bahwa rahmat itu hanya dalam kaitannya dengan Yesus Kristus. Rahmat bagi manusia mengalir dari Salib Kristus. Karena rahmat yang dianugerahkan kepada manusia tidak terlepas dari Kristus, arti rahmat menurut Barth di sini berbeda dengan apa yang dimaksudkan paham rasionalisme Hegel dan Kant sebagai suatu kesalehan fanatik, atau seperti paham relativisme Troeltsch sebagai gerakkan kesadaran manusiawi menuju kesempurnaan. Barth yakin, hanya dalam Yesus Kristus kita mengalami Rahmat yang mendamaikan kita dengan Allah. Relativisme. Pemutlakan relativisme merupakan cetusan kebalikan sikap eksklusivisme. Relativisme memaksudkan keterbukaan. Dalam keterbukaan dicakup pengertian bahwa keselamatan dapat diraih di luar agama Kristen. Pemutlakan relativisme memandang bahwa semua agama pada prinsipnya sama saja. Semua agama mengantar dan mengarahkan manusia kepada keselamatan. Sebab agama pada umumnya mempunyai keserupaan maksud sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan. Dengan pemutlakan relativisme dimaksudkan teori relativisme agama yang digarap secara sistematis oleh Troeltsch (1980)6. Troeltsch di sini dapat dipandang sebagai wakil para teolog yang mengajukan pandangan sikap relatif iman Kristen dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Dalam teorinya tentang relativisme agama, Troeltsch memandang kemunculan agama dalam perspektif evolusioner belaka. Maksudnya agama bagi Troeltsch hanyalah merupakan proses wajar atau proses evolutif dari kerinduan manusia menuju kesempurnaan. Proses menuju 5 Karl Barth, "The Revelation of God as the Abolition of Religion", dalam Christianity and Other Religion, no. 32. Artikel tersebut dari bab 17 no. 2 tentang "The Doctrine of the Word of God", vol 1 dari Church Dogmatics (Edinburgh: Clark, 1961). Kutipan dari Harold Coward, Op. Cit., hal. 24. 6 Ernst Troeltsch, "The Place of Christianity among the World Religions", dalam John Hick & Brian H. (eds.), Christianity and Other Religions (Glasgow: Funt, 1980), hal. 11-31. 9 kesempurnaan dikatakannya sebagai proses manusiawi dan universal. Seluruh sejarah manusia terdiri dari gerakan semacam ini. Dari sebab itu gerakan ini (agama) tidak dapat ditiadakan. Gerakan ini dapat bersifat temporal (misalnya gerakan mesianisme) dapat pula bersifat permanen (agama-agama yang melembaga) atau tradisional (budaya atau kultus). Dalam teori ini, dari sendirinya, agama-agama itu sama saja. Kesamaannya terletak pada sifat relatifnya, agama muncul sebagai proses gerakan manusiawi. Dengan demikian, dalam paham ini, ditolak segala macam bentuk eksklusivisme. Bila semua agama sama saja, pemutlakan kebenaran menjadi siasia. Wahyu tidak ada yang mutlak. Kebenaran dalam agama-agama karenanya bersifat relatif. Bila teori mengenai pemutlakan relativisme ini diterapkan pada agama Kristen dalam hubungannya dengan agama-agama lain, maka Yesus Kristus menduduki posisi yang tidak berbeda dengan tokoh-tokoh pendiri agama-agama lain atau tidak lebih sebagai pencetus gerakan kesempurnaan seperti yang lainnya. Troeltsch tidak menyangkal konsekuensi dari teorinya itu. Menurutnya, Yesus Kristus tidak dapat disamakan dengan Allah begitu saja. Ia serupa dengan para pendiri agama yang lain, yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk evolusi munculnya agama Kristen. Pandangan Troeltsch tentang pemutlakan relativisme ini merupakan kutub lain sikap teologi Kristen terhadap agama-agama lain. Dalam banyak hal, teori ini memang dengan mudah mengantar kepada dialog interreligius. Tetapi relativisme agama tampaknya tidak banyak disukai, sebab sangat gampang menjerumuskan orang kepada sikap-sikap indiferentisme. Penulis melihat suatu pandangan yang melegakan banyak pihak tidak dari sendirinya melukiskan genuitas dan otentisitas kedalaman penghayatan iman. Almarhum Yohanes Paulus II ketika ada dihadapan ribuan pemuda-pemudi Maroko di sebuah stadion di Casablanca (1987), disamping terharu sambil mengucapkan terimakasih, berkata di awal pidatonya, bahwa dirinya adalah seorang Katolik yang bangga akan imannya. Dan, dengan iman Katolik yang dihayatinya, ia mengulurkan tangan untuk bekerjasama membangun dunia yang lebih baik, lebih damai, lebih manusiawi. 2. PLURALISME “Relativistic themes are frequently defended under alternative banners like ‘pluralism’ or ‘constructivism’ (with a particular author's line between relativism and pluralism typically marking off those views he likes from those he doesn't),” demikian kata Chris Swoyer. Dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, Chris Swoyer menulis bahwa tema-tema relativistik kerap dibela dalam jargon-jargon seperti pluralisme dan konstruktivisme (http://plato.stanford.edu/ contents.html#r akses tanggal 9 Maret 2010). Tidak sepenuhnya tepat yang ditulis oleh Swoyer. Sebab, pluralisme memiliki cakupan pemahaman yang tidak linear, tidak tunggal. Pluralisme adalah konsep tentang realitas yang dewasa ini menjadi pergumulan hangat terutama dalam ranah teologi. Berbeda dengan Chris Swoyer, saya meletakkan tema pluralisme dalam kaitannya dengan pergumulan teologis. Dalam pluralisme, kerap juga dicakup fenomen multikultural yang menjadi emblem peradaban hidup manusia dewasa ini. Di belahan dunia Eropa, Amerika dan Australia kehadiran para emigran menandai perubahan tidak hanya komposisi jenis manusia, melainkan juga meracik tampilnya keanekaragaman budaya yang untuk selanjutnya juga nilai-nilai. Di Indonesia, multikulturalisme hampir selalu menjadi ketegangan seputar perkara-perkara sensitif suku, ras, 10 dan agama. Yang pasti multikulturalisme menciptakan ruang-ruang nilai baru yang menjadi pergulatan manusia zaman ini. Pluralisme merupakan produk filsafat postmodern yang mempromosikan equality. Kesederajatan nampak paling jelas dalam pergumulan di wilayah politik. Jika dahulu politik identik dengan urusan maskulin (yang dipromosikan oleh filsafat Aristotelian-Hegelian), kini politik juga mengedepankan feminitas. Perempuan bukan manusia lemah seperti yang dikira, melainkan manusia yang memiliki potensi sama hebatnya dengan laki-laki. Dahulu kala simbol kepahlawanan terlalu maskulinistik (phalus). Derrida, Simone de Bauvoir dan Julia Kristeva adalah filosof-filosof yang mengritik peradaban maskulinistik sebagai sebuah kesombongan societas. Simone de Bauvoir malah secara filosofis menyebut perempuan dengan the second sex untuk menegaskan protesnya atas fatwa nasib perempuan sebagai yang kurang dihitung dalam kancah tata politik. Di beberapa tempat, peraturan syariat yang menempatkan perempuan di wilayah batas-batas sexual dipandang sudah sangat ketinggalan jaman, dan malah tidak menampilkan kesederajatan. Sepertinya perempuan adalah makhluk penghuni planet ini yang masih perlu diatur-atur sedemikian rupa seolah mereka tidak bisa mengatur diri atau tidak tahu aturan. Begitulah kritik dari para eksponen postmodern. Konon dengan aneka aturan para perempuan dilindungi, tetapi sebenarnya dalam kenyataan mereka ditindas, dikekang, dipenjarakan dengan aneka simbol-simbol. Jika ingin menindas perempuan, lindungi mereka! Demikian sergah para filosof postmodern. Format politik berubah. Dari dominasi maskulin kepada gender dan feminisme. Postmodern menyoal filsafat Aristoteles yang menjerumuskan perempuan sebagai yang bukan dari bagian sistem polis, dan mengekskludirnya jauh dari diskusi perihal virtus dan tata hidup bersama. Postmodern juga menertawakan Hegel yang menyepelekan wanita sebagai makhluk tak rasional. Perempuan sama dengan laki-laki dalam kodrat, juga dalam menggarap tata politik. 2.1. Pluralisme dan Religiusitas Karena pluralisme religiusitas juga mengalami pergeseran nuansa penghayatan. Dulu religiusitas dipersepsi sebagai suatu cita rasa ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan. Pada zaman Pencerahan di Eropa agama adalah aksiomatik. Artinya, agama merupakan kondisi yang tidak bisa tidak. Setiap orang beragama (Kristiani). Dewasa ini tidak demikian. Religiusitas tidak bisa diandaikan sekedar percaya kepada doktrin ajaran agama. Religiusitas tidak sekedar itu. Religiusitas mesti performatif dan redemptif. Artinya, apa yang disebut sebagai suatu cita rasa keimanan kepada Tuhan bukanlah sekedar terarah kepada suatu doktrin, suatu dogma, suatu hukum atau syariat yang benar. Religiusitas postmodern memiliki karakter yang menampilkan diri secara konkret sebagai suatu “komoditas layak jual,” bila meminjam terminologi ekonomi. Religiusitas adalah suatu cara hidup. Hidup yang memikat, yang pantas dipeluk, yang layak dijalani. Religiusitas bukan keterpaksaan. Atau, tak pernah boleh berupa suatu keniscayaan. Religiusitas itu menggaet siapa pun untuk memeluknya.7 Dalam istilah Charles Taylor, religiusitas mesti menampilkan sense of fullness. Ringkasnya, religiusitas mesti membuat hidup manusia lebih baik dari ke-areligiusitas-an. Suatu ketakwaan kepada Tuhan tidak bisa sekedar direduksi pada pemenuhan delik-delik ketentuan 7 Satu dua frase di bawah ini adalah kutipan dari pidato filosofis yang saya sampaikan tanggal 28 November 2009. 11 hukum atau syariat. Suatu ketakwaan haruslah pula merupakan suatu kegembiraan, sukacita, realitas yang menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan. Artinya lagi, setiap kesalahan atau pengalaman dosa tidak bisa sekedar dilihat sebagai suatu pelanggaran hukum. Suatu pengalaman dosa merupakan bagian integral dari suatu perjalanan hidup manusia menuju kepada sang sumber suka cita itu sendiri, Sang Khaliknya. Inilah faktor redemptif dari suatu pengalaman religius. Atau, suatu pengalaman religius hampir tidak bermakna sejauh tidak merupakan suatu pengalaman yang menyelamatkan dan membebaskan. Ketaatan kepada Tuhan nyaris tiada arti kalau tidak membangun kehidupan sukacita sehari-hari. Saat ini. Di sini. Religiusitas bukan rigoritas atau radikalitas sikap-sikap militeristik dan teroristik. Religiusitas bukan itu yang menjanjikan kenikmatan surgawi. Religiusitas adalah pengalaman yang menyelamatkan dan membebaskan dari ketidakpastian. Bukan membelenggu pada keniscayaan, kekuatan takdir, keterpaksaan nasib. Manusia menyejarah, mengukir sejarahnya, mencetuskan sejarahnya, bukan merekayasa sejarahnya atau membual tentang masa lampaunya. Tetapi, pada saat yang sama, harus pula diakui bahwa manusia juga terguling dan terjungkal di dalam momen-momen sejarah yang dilakoninya. Manusia bukan hanya subjek pelaku kecemerlangan sejarah, tetapi ia juga subjek penderita dalam sejarahnya. Ia bukan “objek” penderita, sebab di luar manusia dan sejarahnya, tidak dijumpai subjek lain selain manusia. Charles Taylor, tracing phenomenologically sejarah manusia di dunia yang berada dalam tensi (ketegangan) dan rekonsiliasi (kerukunan) tata hidup bersama, mencetuskan relasionalitas Sacred and Secular. Siapakah manusia dalam dunia yang kerap disebut “postsekular” ini (dekulturisasi atau dunia yang mengalami pendangkalan kultural)? Manusia kini adalah manusia yang hidup dalam the enchanted world (dunia yang memukau) yang berhadap-hadapan dengan dunia yang disenchanted (dijenuhkan) oleh produk sekularisme. Dalam bukunya, A Secular Age (2007), Taylor membedah kebekuan modernitas yang terperangah oleh kemajuan, kenyamanan, keindahan artifisialitas teknologi dan ilmu pengetahuan dan pada saat yang sama didera kekeringan, ketandusan, kesunyian, dan kedangkalan, konflik serta perang yang berkepanjangan (Afrika, Timur Tengah, juga sebagian Asia disamping Amerika Latin). Manusia terdampar pada pulau buatannya yang memerangkap dirinya sendiri dalam disposisi naif. Naivitas (kenaifan) lantas seolah identik dengan keseharian. Dalam dunia saat ini, menurut Taylor, manusia seakanakan dicabut dari akar kesuburan rohani dan spiritual kehidupannya. Klaim-klaim modernitas yang menyepelekan the Sacredness tidak meyakinkan, sergah Taylor. Ia juga mengritik bahwa profanasi yang dilakukan para sekularis kehilangan maknanya ketika upaya untuk itu jatuh kepada ideologisasi. Para pencetus profanasi kehidupan mempropagandakan model-model kehidupan yang nyaman sebentar tetapi tidak menyentuh kepada sebuah kesaksian yang memesonakan. Simak bagaimana propaganda “There is probably no God, be happy” di bus-bus di kota London tidak populer. Itu hanya sebuah propaganda yang mengusung cara-cara ideologi masa lalu. Ideologi bukan saja sudah mati melainkan juga sudah ketinggalan jaman. Di lain pihak, ideologisasi juga ditampilkan oleh para eksponen fundamentalis yang teroristik yang justru membuah hidup makin tidak menarik, malah makin menjenuhkan. Charles Taylor, seorang filosof yang mengatakan dirinya sebagai practicing Catholic, mengajak kita seolah tidak berkedip dalam menikmati hamparan kehidupan keseharian manusia yang sarat dengan makna-makna beragam, yang mempromosikan kekayaan sekaligus misteri yang mencengangkan, the sense of fullness (Simak A Secular Age). The sense of fullness, atau cita rasa kepenuhan, di samping memiliki identitas “di sana”, juga mengatakan “di sini” dalam 12 keseharian. Artinya, menurut Taylor “the sense of fullness” bukan menjadi milik manusiamanusia yang jarang atau masa lampau, melainkan dimiliki oleh manusia-manusia saat ini di sini dalam cara-caranya yang unik dan khas. Keseharian lantas menjadi worthwhile (sangat bernilai). Ketika seorang bapak dari Aceh yang kehilangan isteri, ketujuh anaknya, rumah dan sekalian harta bendanya dalam peristiwa tsunami yang sangat dahsyat, berkata dengan begitu jelas, “Oh, betapa Tuhan itu agung dan besar ...,” refleksi apakah yang muncul di benak akal budi atau dalam kesadaran batin kita jika bukan bahwa manusia adalah makhluk refleksif mengagumkan?! The sense of fullness tidak terletak pada pengalaman keindahan atau kenikmatan nanti yang kita sebut surgawi. The sense of fullness is also here, ketika manusia berada dalam kepenuhan sebagai dirinya yang mendeklarasikan keterbatasan di satu pihak dan keagungan Tuhan di lain pihak. Bapak itu tidak kehilangan orientasi hidup dan makna kendati mengalami pengalaman duka dan kecemasan yang luar biasa. Bapak itu tidak mengatakan kenaifan, melainkan mendeklarasikan keluhurannya dan memproklamasikan kebesaranNya. Makna kehilangan berpadu dengan makna kepenuhan. Taylor menyebut seorang bapak tadi adalah manusia yang mengeksplorasi keluhurannya, menyeberangi keterbatasan untuk memeluk kedalaman dan kepenuhannya. 2.2. Pluralisme dalam Teologi Dalam ranah teologi, pluralisme memiliki nuansa positif sebagai bagian dari konteks hidup manusia. Pluralisme merupakan sebuah kesadaran akan pluralitas kenyataan sehari-hari. Pluralisme adalah konteks keseharian hidup manusia. Secara menyolok pluralisme di sini menjadi salah satu tema pergumulan teologis dialogal.8 Avery Dulles (1980)9 menyebut teologi dialog dalam konteks perkembangan terakhir teologi (the recent development in theology). Konteks perkembangan terakhir yang dimaksudkan ialah konteks pluralisme. Pluralisme bukanlah konsep abstrak, melainkan mengalir dari banyak perjumpaan. Simak bagaimana Mendiang Paus Yohanes Paulus II telah mengawali sebuah perjumpaan yang akan menjadi emblem perkembangan teologis modern, perjumpaan doa bersama di Asisi sejak tahun 1986. Semangat berjumpa dengan para pemimpin agama dunia ini juga dilanjutkan oleh penerusnya, Paus Benediktus XVI, yang semula adalah kolaborator dekat Almarhum. Senada dengan Dulles, David Tracy (1988) menegaskan bahwa situasi perkembangan teologi saat ini ialah pluralisme. Pluralisme bahkan telah menjadi apa yang disebut sebagai kebenaran yang tak terelakkan.10 Pluralisme teologi inilah yang mendesak para teolog untuk melakukan dan merefleksikan tema dialog. 8 Bagian ini merupakan kutipan dari tesis yang pernah penulis garap ketika menyelesaikan program S2 teologi (1993) di STFT Widya Sasana dengan judul: “Teologi Dialog. Sintesis Pandangan-Pandangan Dokumen Konsili dan Pascakonsili Vatikan II.” Kutipan tidak persis sama sebab mengalami beberapa revisi dalam pengembangannya. Sedianya revisi ekstensifnya akan diterbitkan sebagai sebuah buku. 9. Avery Dulles, "Ecumenism and Theological Method", dalam Journal of Ecumenical Studies, 17:1, Winter (1980), hal.40-48. 10. David Tracy, Blessed Rage for Other. The New Pluralism in Theology (San Fransisco: Harper & Row, 1988), hal. 3 dan juga The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism (New York: Crossroad, 1989), hal. xi. 13 Dapat dikatakan dialog menjadi salah satu kata kunci utama Konsili Vatikan II. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes mengungkapkan dengan gamblang bagaimana Gereja masuk dalam dialog dengan dunia. Karena berdialog dengan dunia, Gereja memiliki suatu pesan untuk diungkapkan, dibagikan, dikomunikasikan, didialogkan. Alasan Gereja membuka diri untuk menjalin dialog juga diresapi oleh semangat Ensiklik Ecclesiam Suam (21 November 1964), Ensiklik pertama dari Paus Paulus VI. Dalam Ensiklik itu, Gereja diminta untuk "menjalin dialog keselamatan tanpa batas dan tidak menunggu terlebih dahulu untuk diundang". Konstitusi Dogmatik Lumen Gentium melukiskan dengan jelas bahwa semua manusia dipanggil menjadi umat Allah yang baru (LG. 13), akan tetapi sekaligus diakui bahwa tidak semua tergabung dalam cara yang sama (LG. 14-16). Dengan demikian Gereja tidak menyangkal keanekaragaman atau pluralitas pencetusan umat Allah yang baru. Maka, secara implisit kita menyimak Gereja – dalam Konstitusi Dogmatik Lumen Gentium ini – yang sungguh mengajak umat beragama lain untuk bersama-sama membangun suatu dialog keselamatan. Dikatakan secara implisit, sebab penjelasan yang lebih gamblang dan eksplisit diungkapkan dalam Dekrit Nostra Aetate (28 Oktober 1965). Dekrit ini secara tegas menegaskan perlunya segera mengusahakan dialog. Dalam konteks Asia, kebutuhan untuk menggalang dialog amat mendesak. Sebab Gereja Asia berhadapan langsung dengan tantangan pluralisme di segala bidang kehidupan. Juga teramat menyolok dalam pluralisme agama dan kultur. Sidang para Uskup Asia (FABC V) di Lembang Bandung 17-27 Juli 1990 menyadari itu semua. Sidang yang mengambil tema "Menanggapi Tantangan Gereja Asia: menyongsong Milenium ketiga" ini menaruh perhatian pada kondisi pluralisme Asia dan mencoba mengajukan pandangan-pandangan pastoral bagaimana sebaiknya Gereja Asia hadir dan menaggapinya.11 Dalam pengamatan Gratsch, sejak Vatikan II teologi berkembang dari titik tolak sejarah ke pangakuan dan penghargaan akan pluralisme.12 Jadi konteks pembicaraan tentang teologi dialog ialah pluralisme dalam teologi. Dengan pluralisme teologi dimaksudkan titik tolak, bahasa, metode, arah, dan lingkungan sosial teologis yang berbeda-beda.13 Perbedaannya begitu rupa sehingga tidak ada satu bahasa teologis filosofis pun yang dapat merangkum segalanya. Karl Rahner menengarai, untuk mencegah kesimpangsiuran kebenaran perlu dikembangkan sikap-sikap toleransi timbal balik, kesediaan untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi, dan memupuk sikap-sikap kritis satu sama lain di antara para teolog dan Vatikan. Sikap-sikap menutup diri dari kritik, menawarkan kebenaran sebagai harga mati, mengutuk perbedaan-perbedaan, membumi hangus upaya-upaya inkulturatif dan penghayatan iman atas pondasi kultur sendiri, dan yang semacamnya adalah sikap-sikap yang tidak menguntungkan dalam arus pluralistik teologi yang demikian deras dewasa ini. Sebab perbedaan-perbedaan pendekatan dalam teologi muncul sebagai yang tak terhindarkan.14 11. Lih. Michael Amaladoss SJ., "The Church And Pluralism in The Asia of The 1990s" (Fifth Plenary Assembly: Workshop Discussion Guide) dalam FABC Papers, no. 57e, 1-19. Juga dapat disimak R. Hardawiryana SJ., "The Church Before The Changing Asian Societies Of The 1990s", dalam FABC Papers, no.57a, 4-5. 12. Edward J. Gratsch, Gratsch, Edward J., Principles of Catholic Theology (New York: Alba House, 1981), 20. 13. Karl Rahner, "Anonymous and Explicit Faith", vol. 16 dari Theological Investigations (New York: Seabury Press, 1979), 239. 14. Ibid., 240. 14 Sedangkan David Tracy mengusulkan "model baru hermeneutika yang dapat disharingkan di tengah-tengah perbedaan dan pertentangan."15 Dalam pengamatan Tracy, pluralisme selain telah membangkitkan perubahan paradigma dalam teologi, juga menciptakan krisis-krisis baru. Krisis baru ini pada prinsipnya bertumpu pada problem hermeneutika tentang hubungan antara tradisi dan situasi dewasa ini. Keanekaragaman penafsiran tentang tradisi dan situasi, menurut banyak pengamat, sebagaimana dikatakan Tracy dalam simposium di Universitas Tubingen Jerman (dengan tema "Is There A Basic Christian Concensus Theology Today In Spite Of All Our Differences?"),16 telah menimbulkan kekacauan dalam teologi.17 Karena kesimpangsiuran dalam interpretasi tradisi dan situasi dewasa ini diamati sebagai problem yang mendasar dalam pluralisme teologi, Tracy melontarkan suatu model hermeneutika baru yang dapat disharingkan di tengah perbedaan dan pertentangan teologis.18 Mengapa teologi Neoskolastik19 yang telah lama populer dalam Gereja sejak Abad Mediovale kehilangan pamor? Tentulah itu merupakan konsekuensi-konsekuensi yang mengalir dari semangat pembaharuan Vatikan II. Dekrit tentang kebebasan Agama (Nostra Aetate) jelas langsung menunjukkan penghargaan Gereja terhadap keanekaragaman agama. Di mana-mana dikembangkan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan iman. Dalam situasi baru semacam ini, Neoskolastik dipandang tak sanggup lagi menjawab aneka tantangan baru. Neoskolastik yang dalam uraian teologisnya banyak menguraikan kebenaran-kebenaran (yang sering diajukan sebagai kebenaran mutlak) dianggap telah ketinggalan jaman. Teologi Neoskolastik tampak konkret dalam Katekismus, uraian teologis dalam rumusan-rumusan kalimat ketat dan valid. Jika salah menyebut, dulu teman kami (ketika mengikuti kursus katekumenat, harus berdiri di depan kelas sepanjang pelajaran berlangsung!). Dalam kondisi yang berubah, plural, dan kompleks semacam ini, refleksi iman membutuhkan sumbangan-sumbangan aneka disiplin ilmu dan membuka diri terhadap keanekaragaman. Pemutlakan kebenaran umumnya dipandang sia-sia. Menurut Hans Küng dan banyak teolog lain yang ambil bagian dalam simposium Tubingen 1989, masa kejayaan teologi Neo-skolastik telah tumbang. Menyusul berikutnya paradigma-paradigma baru dalam teologi.20 Teologi dialog dapat dikatakan merupakan salah satu bentuknya, biarpun belum menemukan wujudnya yang konkret. Kapan teologi Neo-skolastik tak lagi menguasai metode berteologi dalam kalangan para teolog? Saat kapan persisnya pastilah tidak mudah ditentukan. Yang pasti sampai dengan Ensiklik Humani Generis dari Pius XII (1950), Neo-skolastik masih ditegaskan sebagai teologi resmi Gereja. Dan filsafat skolastik 15. David Tracy, "Some Concluding Reflections on the conference: Unity amidst Diversity and Conflict?" dan "Hermeneutical Reflections in The New Paradigm", dalam Hans Küng and David Tracy (eds.), Op. Cit., 34-62 dan 461-471. 16. Simposium yang melibatkan pakar-pakar di bidang filsafat, teologi, sosiologi, agama dari Katolik dan Protestan itu berlangsung awal Januari 1989. Hasil-hasilnya dapat disimak dalam buku Paradigm Change in Theology. A Symposium of the Future (Edinburgh: T. &T. Clark. Ltd. 1989). 17. Tentang hubungan tradisi dan situasi dewasa ini, menurut Tracy paling sedikit ada tiga macam penafsiran. Hubungan pertama berupa konfrontasi (dipandang sebagi dua hal yang terpisah, berbeda dan bahkan bertentangan). Hubungan kedua sering kali disebut analogi (mencoba menemukan keserupaan dalam perbedaan); dan ketiga, tradisi dan situasi dilihat sebagai identik. 18. Gagasan Tracy ini menemukan penjabarannya dalam dua bukunya Blessed Rage for Order. The New Pluralism in Theology, (San Fransisco: Harper & Row, 1988) untuk teologi fundamental; dan The Analogical Imagination. Christian Theology and Culture of Pluralism (New York: Crossroad, 1989) untuk teologi sistematis. 19 Teologi neosklastik artinya teologi yang mengedepankan rumusan-rumusan dogmatis filosofis sedemikian rupa sehingga refleksi iman menampilkan suatu bahasa yang valid. 20. Munculnya paradigma-paradigma baru dalam teologi ini dapat dilihat misalnya pada M. Dhavamony, "Indian Perspektives in the New Paradigms of Theology"; Mengenai benih-benih munculnya teologi dialog, dapat disimak pada Hans Küng, " A New Basic Model for Theology: Divergencies and Convergencies", dalam Hans Küng dan David Tracy (eds.), Paradigm Change in Theology. A Symposium For The Future (Edinburgh: T.&T. Clark Ltd., 1989), hal. 424-436 dan 439-451. 15 merupakan filsafat abadi yang tetap wajib diajarkan di seminari-seminari dan universitasuniversitas Katolik. Tumbangnya superioritas di bidang-bidang sekular telah pula menghancurkan superioritas agama Kristen. Dan untuk pertama kalinya sejak itu, agama Kristen dalam mewartakan Kerajaan Allah merasa bahwa agama-agama lain juga memiliki misi yang serupa dengan misinya, yakni membangun kesejahteraan, memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan cinta kasih.21 Dan mulailah babak-babak baru dalam dialog diupayakan. Aneka perbedaan diakui dan disadari tetapi tidak dipandang sebagai kendala untuk menjalin kerjasama dalam dialog. Paradigma-paradigma baru dalam beriman dan berteologi mulai ditelusuri dan dicari. Berhadapan dengan pluralisme, Hans Küng mengusulkan suatu konsensus fundamental dalam teologi Katolik. Konsensus fundamental ini ditawarkannya sebagai yang akan menunjukkan jalan bagi teologi Katolik menuju teologi ekumenis, dialog dengan agamaagama.22 Menurut Küng, tiadanya bahasa teologis resmi dalam arus pluralisme dewasa berarti tumbangnya teologi Neo-skolastik, yang merupakan teologi resmi Gereja selama ini. Karena itu saat ini dibutuhkan suatu konsensus teologis untuk menjadi semacam standar penilaian sahih tidaknya suatu refleksi teologis di satu pihak, dan menjaga penghargaan keanekaragaman di lain pihak.23 Konsensus fundamental ini, menurut Küng, berada dalam dua kutub sumber. Sumber pertama ialah pengalaman tradisional umat Kristen awali yang didalamnya dijumpai bagaimana Wahyu Allah menjadi konkret dalam hidup Yesus dan sejarah bangsa Yahudi. Sumber kedua merupakan pengalaman umat Kristen dewasa ini dan dalam pergaulannya dengan umat bukan Kristen. Bila dalam sumber kedua dicakup pula pengalaman umat bukan Kristen, itu memaksudkan dengan tegas bahwa konsensus teologis memang diperuntukkan juga bagi suatu teologi dialog dengan agama-agama. Diakui pula oleh Küng bahwa pengalaman umat Kristen dewasa ini sangat plural. Pluralitas pengalaman umat Kristen tidak mungkin dirangkum dalam satu bahasa penafsiran teologis. Suatu interpretasi teologis haruslah menyimak keanekaragaman pengalaman manusia, mendengarkan kerinduan-kerinduannya yang terdalam, belajar dan menaruh perhatian pada masalah-masalah konkret dalam masyarakat. Dengan merujuk pada gagasan Edward Schillebeeckx dalam buku Jesus, an Experiment in Christology, 1979), Hans Küng bahkan menegaskan bahwa eksegese Kitab Suci dan penafsiran hidup Yesus haruslah memperhitungkan dimensi horisontal pengalaman konkret manusia. Penjelasan tentang wahyu Sabda Allah, misalnya, harus dikatakan bahwa Sabda Allah bukan hanya sekedar Tindakan Allah yang menjelma, melainkan sungguh-sungguh penyataan Pribadi Allah yang menyentuh dan menyapa sejarah pengalaman hidup manusia. Atau, dengan demikian konsekuensinya, tidak ada wahyu bila tidak menyentuh pengalaman konkret manusia. 21. Lih. Landon Gilkey, "The Paradigm Shift in Theology" dan John Cobb, "Response to J.B. Metz and Landon Gilkey", keduanya dalam Ibid., 367-388. 22. Usulan Hans Küng ini untuk pertama kalinya dilontarkan pada bulan Juli 1979 dalam suatu diskusi tentang "konsensus dalam teologi" dengan Edward Schillebeeckx, David Tracy, Leonard Swidler, dll. Lih. Journal of Ecumenical Studies, 17:1, Winter (1980). Jadi enam bulan sebelum Hans Küng dilarang mengajar oleh Vatikan (18 Desember 1979) karena dipandang telah menyimpang dari kebenaran-kebenaran integral iman Katolik. Sebenarnya ketika Hans Küng menerbitkan bukunya On Being a Christian (1973), Vatikan sudah menyatakan keberatan-keberatannya terutama yang menyangkut problem otoritas dalam Gereja. Dan bahkan CDF (The Congregation for the Doctrine of the Faith) pada tahun itu juga sudah menerbitkan suatu deklarasi membela ajaran Katolik yang benar tentang Gereja. Tetapi tahun 1979 merupakan puncaknya, Profesor Hans Küng secara tegas dilarang mengajar. 23. Hans Küng, "Toward A New Concensus In Catholic (and Ecumenical) Theology", dalam Journal of Ecumenical Studies, 17:1, Winter (1980), 1-17. 16 Pendek kata suatu konsensus teologi hanya mungkin dijalankan dengan analisis atas pengalaman konkret manusia dewasa ini (pertama), panggalian pengalaman umat Kristen awali dalam Kitab Suci dan dalam kesatuannya dengan Tradisi Kristen (kedua), dan menggarap apa yang disebutnya sebagai "konfrontasi timbal balik" dari sumber pertama dan kedua (ketiga). Gagasan Hans Küng tentang konsensus teologi memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan teologi Katolik. Implikasi ini bahkan dikatakannya sebagai prinsip-prinsip yang membimbing teologi kontemporer dewasa ini:24 1. Teologi tak boleh menjadi ilmu iman yang hanya diperuntukkan bagi umatnya, melainkan harus pula dapat dipahami oleh bukan umatnya dan bahkan orang yang tak beriman sekalipun. Teologi harus dapat menjangkau dan menyentuh segala lapisan manusia dengan aneka pengalaman agamanya. 2. Teologi tak boleh melulu mengangkat persoalan-persoalan iman atau sekadar mempertahankan sistem gerejani yang mapan, melainkan harus sungguh berusaha mencari kebenaran. Dan untuk itu teologi harus terbuka untuk diskusi-diskusi ilmiah. 3. Pandangan-pandangan teologis yang bertentangan dengan ajaran resmi Gereja tak perlu dielakkan, apalagi langsung divonis sesat atau heretik. Pandangan-pandangan itu harus diuji dalam suatu diskusi yang terbuka dan dalam semangat toleransi. 4. Para teolog tak boleh hanya sekedar mempromosikan pendekatan-pendekatan interdisipliner dalam analisisnya, melainkan harus sungguh-sungguh melaksanakannya. Para teolog harus terbuka dan banyak menjalin dialog. 5. Dengan ini dimaksudkan bahwa kita lebih membutuhkan dialog yang saling mengembangkan (antarberbagai disiplin ilmu dan antaragama) daripada bersitegang dalam sikap-sikap konfrontatif mengenai rumusan kebenaran iman. 6. Persoalan-persoalan masa lampau harus tak boleh mengalahkan perhatian kita terhadap aneka peristiwa dewasa ini di sini dalam masyarakat kita. 7. Kriteria kebenaran kita tak boleh diletakkan pada tradisi teologis atau pandangan institusi gerejani, melainkan pada Injil yang ditafsir dengan metode historis kritis. 8. Injil tak boleh diproklamasikan dalam arkhaisme biblis yang kaku atau juga tidak dalam dogma-dogma skolastik filosofis metafisis. Injil harus diwartakan dalam ungkapan-ungkapan bahasa manusia dewasa ini, bahasa yang menyentuh pengalaman hidup sehari-hari. 9. Harus dihindarkan pemisahan-pemisahan antara teori dan praksis, antara dogmatika dan etika, antara pietas personal dan karya institusi. 10. Kita harus mengelakkan mentalitas gheto atau kecenderungan mengurung diri dalam kelompok yang eksklusif. Kita mesti berusaha membuka diri dan memupuk visi-visi ekumenis dan dialogal dengan sesama yang tidak seiman. David Tracy menggali tema pluralisme teologi. Dalam bukunya mengenai kriteria umum untuk teologi fundamental, Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology, Tracy mengajukan lima tesis model teologi revisionis. Revisi ini dikatakannya sebagai model hermeneutika baru yang dapat disharingkan di tengah-tengah perbedaan. Revisi ini membantu mencegah kekacauan teologis di satu pihak dan menghindarkan diri dari kecenderungan untuk membatasi keanekaragaman dalam berteologi di lain pihak. Dikatakan revisionis, sebab aneka perubahan baru yang terjadi dewasa ini - sebagaimana diterangkan sebelumnya - meminta pembenahan-pembenahan baru. Revisi ini meliputi bidang pengalaman dan bahasa manusia (pertama) dan interpretasi Kitab Suci dan Tradisi Kristen (kedua). Kedua bidang yang dicakupnya dalam pengertian teologi fundamental ini dijabarkannya dalam lima tesis:25 - Tesis pertama: Dua sumber utama teologi ialah Kitab Suci dan Tradisi Kristen (pertama), dan pengalaman serta bahasa manusia (kedua). 24. 25. Ibid., 13. David Tracy, Blessed Rage for Order. The New Pluralism in Theology (San Fransisco: Harper & Row, 1988), 43-56. 17 - - Tesis kedua: Tugas teologi ialah menggarap hubungan kritis (korelasi kritis) kedua sumber itu. Tesis ketiga: Metode penyelidikan tentang pengalaman dan bahasa manusia dapat dilukiskan sebagai fenomenologi dimensi religius dalam bahasa dan pengalaman manusia, baik pengalaman yang bersifat biasa sehari-hari maupun pengalaman ilmiah saat ini. Tesis keempat: Metode penyelidikan tentang tradisi-tradisi Kristen dapat dilukiskan sebagai penyelidikan historis dan hermeneutik mengenai teks-teks Kristen klasik. Tesis kelima: Untuk menentukan status kebenaran hasil-hasil penyelidikan tentang arti kedua sumber (Tradisi dan pengalaman serta bahasa manusia pada umumnya), digunakan suatu model refleksi transendental dan metafisis.26 2.3.Pluralisme dan Fenomen Perjumpaan Fenomena pluralisme agama tidaklah baru. Tetapi kesadaran akan pluralisme agama semakin diperteguh dengan gejala baru, pertemuan antarumat beragama. Dalam kerangka konteks perubahan paradigma berteologi, pertemuan antar umat beragama semakin mendesakkan perlunya teologi dialog. Beriman dialogal menjadi tuntutan konkret dan mendesak. Pertemuan antarumat beragama telah menandai bangkitnya teologi dialog. Banyak agama dewasa ini menampakkan tanda-tanda gerakan yang lebih positif. Mereka meninjau ulang kecenderungan-kecenderungan terselubung atau terang-terangan untuk menyatakan diri sebagai satu-satunya agama yang benar. Sebagai satu-satunya agama yang menawarkan Wahyu yang paling benar. Sebagai satu-satunya yang mengantar kepada pembebasan dan keselamatan. Dan, sebagai satu-satunya pemegang hak paten kebenaran. Mereka cenderung untuk beralih dari cara berpikir salah benar kepada apa yang dapat disumbangkan untuk membangun dunia. Bila ada suatu agama yang berkutat dalam pandangan lama, ia telah ketinggalan jaman. Dunia telah mengakui pluralisme agama. Bila ada suatu agama yang memandang dirinya paling benar dan pada saat yang sama memvonis yang lain sebagai kafir atau sesat, agama tersebut telah jatuh pada kesempitan. Dekade delapan puluhan adalah saat di mana dunia mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada waktu itu terjadi hancurnya batas-batas budaya, rasial, bahasa, dan geografis. Tembok Berlin telah runtuh. Sementara itu peradaban filsafat dan budaya telah menghasilkan produk-produk polarisasi kultur. Muncul istilah-istilah seperti globalisasi, multikulturalisme, pluralisme, dan seterusnya. Dunia telah mengalami perubahan ke arah komunitas dunia. Baik dunia Barat maupun Timur kini tak bisa lagi menutup diri. Dunia Barat tak dapat menganggap diri lagi sebagai pusat budaya dan pemilik agama yang benar dengan peribadatan yang absah. Dewasa ini setiap orang adalah tetangga dekat bagi yang lainnya. Tetangga dalam arti sebagai komponen masyarakat sekaligus dalam arti sebagai tetangga rohani. Dengan kata lain, setiap agama sebagaimana juga setiap orang, merupakan suatu kemungkinan eksistensial yang ditawarkan kepada setiap orang. Agama-agama asing sudah menjadi bagian dari kehidupan 26. Untuk menyimak apa yang dimaksud Tracy dengan refleksi transendental metafisis, lih. Ibid., 91-170 (part.II). 18 sehari-hari.27 Bahkan karenanya, dewasa ini pola-pola asing atau tidak asing dalam hal beragama, hampir tidak dijumpai lagi. Raimundo Panikkar menyebut ada tiga kemungkinan sikap yang ditampilkan suatu agama bila mengalami pertemuan dengan agama lain. Sikap pertama ialah eksklusif. Sikap eksklusif berarti sikap yang menutup diri, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya, dan mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran satu-satunya. Eksklusivisme tidak memberi tempat kepada toleransi. Sikap kedua berupa sikap inklusif. Sikap kedua ini dapat dikatakan kebalikan sepenuhnya dari sikap eksklusif. Suatu agama dengan sikap inklusif memberi tempat bagi toleransi. Inklusivisme agama menghindarkan diri dari kecenderungan untuk menegaskan diri sebagai pemilik kebenaran universal. Sikap inklusif menampilkan suatu agama untuk bertindak bagaikan suatu payung yang menaungi, mengakui, menghargai aneka perbedaan ajaran iman di bawahnya. Sikap ketiga merupakan paralelisme. Panikkar menjelaskan bahwa sikap paralelisme menjaga batas-batas yang jelas di satu pihak dan menampilkan pembaharuan-pembaharuan yang konstan dari suatu agama di lain pihak.28 Sikap paralelisme tampak nyata dalam kecenderungan suatu agama untuk mencari titik-titik padanan atau titik-titik pertemuan dengan agama-agama lainnya. Sikap demikian dapat mengantar kepada suatu sikap yang dialogal terhadap agamaagama lain.29 Agama Kristen demikian juga. Ia tak mungkin mengelak dari perjumpaan dengan agamaagama lain. Harold Coward dalam bukunya Pluralism (1985) melukiskan perjalanan agama Kristen sejak awalnya hingga perkembangan-perkembangan mutakhir.30 Dijumpai bahwa sesungguhnya pertemuan antarumat beragama tidaklah baru disadari. Namun sejak awalnya sudah ditegaskan semangat misioner eksklusif dalam perjumpaan dengan agama-agama lain. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa kehadiran para misionaris dalam jumlah yang memadai di seluruh dunia akan menghasilkan pertobatan semua orang kepada Kristus. Dewasa ini orang-orang Kristen menyadari bahwa agama-agama Yahudi, Islam, Hindu, dan Budha tetap berkembang dengan pesat meskipun upaya-upaya misi Kristen menggebu. Menurut Coward, pesatnya perkembangan kepustakaan akibat perjumpaan dengan agama-agama lain membuat para teolog Kristen menarik kesimpulan bahwa teologi Kristen tidak dapat terus dirumuskan terpisah dari agama-agama lain. Dan perkembangan teologi Kristen di masa yang akan datang akan merupakan hasil langsung dari dialog yang serius dengan agama-agama lain.31 27. Harold Coward, Pluralisme. Tantangan Bagi Agama-Agama (terj. Bosco Carvallo) (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 6. Raimundo Panikkar, The Intrareligious Dialogue (New York: Paulist Press, 1978), xiii-xix. 29. Mengenai pertemuan antarumat beragama, Panikkar menyebut ada tiga macam. Model pertama disebutnya sebagai model fisik atau model pelangi. Dikatakan model pelangi, sebab pertemuan antarumat beragama itu membentuk formasi pelangi, berjejer satu dengan yang lain, indah. Model kedua disebut model geometris atau invarian topologis. Pada pertemuan model kedua ini agamaagama berinteraksi, saling mempengaruhi. Model ketiga disebutnya sebagai model antropologis dalam bahasa-bahasa. Maksudnya pertemuan itu terwujud dalam pertemuan manusia-manusia yang berkomunikasi satu sama lain. Lih. Ibid., xix - xvii. Panikkar juga menjelaskan apa yang dimaksud sesungguhnya dengan pertemuan antarumat beragama. Menurutnya pertemuan antarumat beragama yang sesungguhnya ialah 1) harus terhindar dari sikap-sikap apologetis baik itu yang sifatnya khusus maupun umum, 2) para partisipan mesti terbuka terhadap aneka tantangan pertobatan, 3) menegaskan dimensi historis perlu, tapi tidak cukup, 4) tak boleh sekedar merupakan simposium filsafat atau teologi, 5) tak hanya merupakan upaya sepihak, misalnya dari Gereja, 6) MELAINKAN harus merupakan suatu pertemuan religius dalam iman dan harapan serta cinta kasih. Lih. Ibid. 3151. 30. Harold Coward, Op. Cit., 31-51. 31. Sinyalemen Coward ini didasarkan pada gagasan para teolog baik protestan maupun Katolik, seperti Paul Tillich, The Future of Religions (New York: Harper & Row, 1966); Klaus Klostermaier, "A Hindu Christian Dialogue on Truth", dalam Journal of Ecumenical Studies, 12 (1975), 157-173; Hans Küng, On Being A Christian (New York: Doubleday, 1976); Karl Rahner, "Anonymous and Explicit Faith", vol. 16 dari Theological Investigations (New York: Seabury Press, 1979); Raimundo Panikkar, 28. 19 Pertemuan antarumat beragama dunia tidak dapat disangkal telah merobek tabir eksklusivisme agama. Agama-agama mulai mengembangkan sikap keterbukaan. Mereka mulai menampilkan diri sebagai institusi yang bersedia mendengarkan sapaan keanekaragaman. Mereka berusaha hidup berdampingan dan menjalin kerjasama. Puncak sekaligus awal yang menandai masa depan hidup keterjalinan agama-agama besar dunia dapat dikatakan terjadi pada waktu diselenggarakan Pertemuan dan Doa Bersama Para Pemimpin Agama-Agama dunia di Asisi, Oktober 1986. Pertemuan yang disponsori oleh Paus Yohanes Paulus II itu ditandai dengan melakukan doa bersama dan menyerukan satu kata, damai. Gereja Katolik memasuki era baru, mencoba dalam setiap kesempatan dialog atau mengadakan pertemuan dengan agama-agama, menjabarkan semangat Asisi 1986. Ketika memperingati 25 Tahun Hari Perdamaian Sedunia (1 Januari 1992), Yohanes Paulus II sekali lagi menegaskan penting dan perlunya mempertahankan serta menjabarkan semangat Asisi 1986 dalam upaya menggalang perdamaian di dunia. Tiada perdamaian di dunia tanpa perdamaian antar agama-agama.32 Maka pentingnya menggalang dialog interreligius tidak bisa ditunda lagi. Pluralisme agama tidaklah baru disadari oleh Gereja Asia. Hal ini tampak jelas dalam pertemuan pertama para Uskup Asia (ABM I / Asian Bishops' Meeting) di Manila 29 Nopember 1970. Pada waktu itu diserukan tekad bersama para Uskup Asia untuk menggalang dialog dan kerja sama dengan agama-agama. Para Uskup Asia menyadari bahwa dalam inkulturasi kebudayaan dan pewartaan Injil di Asia telah terdapat banyak keraguan dan kesalahan di masa lampau. Dari sebab itu, sejak awalnya para Uskup Asia sudah merasakan dialog interreligius merupakan kebutuhan yang perlu dan mendesak: Kami bangga menjadi warga Asia. Sebagai komunitas umat Katolik Asia, kami menginginkan untuk makin lama makin dapat mengintegrasikan diri ke dalam komunitas yang lebih besar di sekeliling kami. Dan juga secara kultural menjadi bagian dari Asia. Hal ini telah dimulai sejak saat ini. Kendati perlahan, namun arah cita-cita ke sana sudah meraih kepastian sekarang. Kami berusaha mulai dari sekarang untuk menjalin dialog yang lebih terbuka, jujur, dan terus-menerus dengan saudara-saudara kami dari agama-agama lain. Agar dengan demikian kami dapat belajar satu sama lain untuk menimba kekayaan spiritual dan untuk menggalang kerja sama sebaik mungkin dalam tugas-tugas yang sama, mengupayakan perkembanganperkembangan yang lebih manusiawi.33 Dapat dikatakan sampai dengan sekarang, para Uskup Asia telah beberapa puluh tahun mendalami masalah dialog interreligius. Melalui OEIA (Office of Ecumenical and Interreligious Affairs), FABC (Federation of Asian Bishops' Conferences) berusaha merenungkan, menganalisis dan merumuskan kembali dialog interreligius dalam terang Konsili Vatikan II dengan membentuk apa yang disebut BIRA (Bishops's Institute for Interreligious Affairs). BIRA sesungguhnya merupakan sederetan pertemuan atau seminar yang diselenggarakan oleh OEIA. Tetapi sebagaimana BIMA (Bishops' Institute for Missionary Apostolate) untuk karya kerasulan misioner dan BISA (Bishops' Institute for sosial Action) untuk karya sosial atau tindakan sosial, The Trinity and Religious Experience of Man (London: Darton, Longman, and Todd, 1973); dapat pula ditambahkan Leonard Swidler (ed.), Toward a Universal Theology of Religion (New York: Orbis Books, 19870); Eugene Hillman, Many Paths. A Catholic Approach to Religious Pluralism (QC. Philippines: Claritian Publications, 1991). 32. Lih. Yohanes Paulus II, "Believer United in Building Peace", dalam Catholic International, 3:3, 1-14 Februari 1992, 102-105. 33. Antonio B. Lambino, "Dialogue, Discernment, Deeds: An Approach to Asian Challenges Today", dalam FABC Papers no. 56, 1990, 2-3. 20 demikian juga BIRA menjadi tonggak kebijakan para Uskup Asia untuk dialog interreligius. Buah pertemuan BIRA itu tidak hanya untuk Gereja Asia, melainkan juga seluruh dunia.34 Dari pendiriannya tahun 1978 hingga sekarang 1992, telah diselenggarakan empat BIRA I - III khusus mendalami masalah dialog dengan salah satu agama besar di Asia. Sedangkan BIRA IV khusus mendalami masalah dialog yang dilaksanakan melalui 12 seminar nasional dan internasional. Berikut ini ialah rangkaian tema-tema yang dibahas dalam BIRA I - IV. Dari pengenalan akan tema-tema ini kita dapat tahu bagaimana perkembangan teologi dialog di Gereja Asia telah diperjuangkan dengan serius. Bukan hanya itu, melainkan juga bagaimana teologi dialog perlahan-lahan menemukan bentuknya yang lebih konkret.35 BIRA I (11-19 Okt. 1979) di Sampran, Thailand: To deepen dialogue with Budists BIRA II (13-21 Nop. 1979) di Kuala Lumpur, Malaysia: To deepen dialogue with Muslims BIRA III (15-20 Nop. 1982) di Madras, India: To depeen dialogue with Hindus; 26 Nop - 4 Des. 1983 di Varanasi, India: - To examine the nature and purpose of Christian presence and witness among Muslims BIRA IV.1 (23-30 Okt. 1984) di Sampran, Thailand: To explore dialogue in the context of the mission of the Church in Asia BIRA IV.2 (17-22 Nop. 1985) di Pattaya, Thailand: The Church at the service of God's Reign BIRA IV.3 (2 - 7 Nop. 1986) di Hongkong: Discerning the spirit at work in and beyond the Church in Asia BIRA IV.4 (29-31 Agust. 1987) di Tagaytay, Philipina BIRA IV.5 The nature of the Church, a community in pilgrimage di India. BIRA IV.5, ini diganti dengan sebuah seminar 4 hari: "Living together for greater harmony" yang diselenggarakan oleh komisi dialog dari Konferensi Wali Gereja di India BIRA IV.6 (5 -10 Juli 1987) di Singapura: Living and working together with sisters and brothers of other faiths BIRA IV.7 (28 Okt.-3 Nop. 1988) di Tagaytay, Philipina: Living and working together with sisters and brothers of other faiths BIRA IV.8, di India dan Philipina dan IV.9 Direncanakan sebagai pertemuan nasional, tapi dibatalkan karena keadaan politik yang sedang kacau BIRA IV.10 (24-30 Juni 1988) di Sukabumi: Theology of Harmony BIRA IV.11 (1-7 Juli 1988) di Sukabumi: Theology of Harmony BIRA IV.12 (21-27 Peb. 1991) di Hua hin, Thailand: Fresh horizons for communion and cooperation Dan seterusnya. Dari tema-tema yang ditampilkan di atas jelaslah bahwa dalam Gereja Katolik Asia telah tumbuh kesadaran baru yang makin mantap akan perhatian terhadap pluralisme agama. Diakui bahwa agama-agama di Asia mempunyai peranan yang menentukan bagi karya besar Allah dalam membawa damai, kebersamaan, dan hidup yang lebih manusiawi bagi semua bangsa di Asia, bahkan bagi seluruh keluarga bangsa manusia. Sebagai kelanjutan pandangan ini, muncullah keyakinan adanya kebenaran yang tak dapat diingkari bahwa Roh Allah berkarya dalam semua tradisi keagamaan. Roh yang menggerakkan para beriman setia dari setiap tradisi tersebut bergerak ke arah keterlibatan yang lebih besar pada kebenaran dan kesadaran yang lebih otentik akan adanya kebersamaan antara pemeluk sesama tradisi maupun di luar tradisinya sendiri. Karena Roh itu pula Gereja Asia telah bergerak ke arah Gereja yang dialogal.36 34. CB. Putranto, The Idea of The Church In The Documents of the FABC 1970-1982 (Roma: Dissertatio ad Doctoratum In Facultate Theologiae Pontificae Universitatis Gregorianae, 1985), hal. 168. 35. Lih. Hak Kerukunan, XII: 69,70,71, th. 1991, hal. 26-27. 36. Ibid., hal. 30; lihat pula Aloysius Pieris, SJ., Love Meets Wisdom. A Christian Experience of Budhism (QC. Philippines: Claritian Publications, 1989), hal.39-42. 21 Dari pemaparan di atas jelas bahwa beriman Kristen memiliki suatu refleksi yang tak terpisah dari pengalaman dialogal hidup sehari-hari. Hubungan dengan umat agama-agama lain meneguhkan, menantang, mengembangkan, menciptakan, dan mentransformasikan ranah berteologi baru. Penghayatan iman Kristen menjadi lebih terbuka, merangkul, mendalam, dan dialogal. 2.4. Pluralisme dan Teologi Harmoni Dalam perspektif BIRA (Bishops' Institute for Interrelegious Affairs) IV/10 dan 11, teologi dialog menemukan bentuknya dalam teologi harmoni atau teologi keselarasan.37 Dengan harmoni, dimaksudkan sekaligus secara negatif tiada pertikaian, tiada persengketaan, mencegah permusuhan dan secara positif kerjasama, dialog persaudaraan, berjuang bersama-sama demi keadilan dan cinta kasih. Harmoni di sini lebih dimaksudkan sebagai hubungan yang selaras antarpribadi dalam kebersamaan dengan menggalang tekad dan cita-cita yang sama. Titik tolak BIRA IV/ 10 dan 11 dalam membangun teologi harmoni ini didasarkan terutama pada kesadaran akan warisan asli budaya tradisional Asia. Dalam pengamatan BIRA IV/10 dan 11, warisan budaya tradisional Asia pada prinsipnya mengajarkan keselarasan universal. Keselarasan ini tampak bukan hanya dalam hal hubungan antara alam dan manusia, melainkan juga antarmanusia. Realitas tampil sebagai satu kesatuan dalam "puisi" keselarasan (Rta; Tao). Kesatuan realitas ini direfleksikan dalam pribadi manusia dalam perasaan, kesadaran, dan jiwanya yang menyatu dan memiliki keterarahan pada hubungan personal dengan sesamanya. Bila kesatuan dan harmoni diwujudkan dalam hubungan antarpribadi manusia yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan cinta, itu disebut sebagai Dharma atau Dhamma. Ditambahkan bahwa masyarakat Asia pada umumnya juga memiliki kesamaan semangat kerohanian yang mendalam, mistisisme, dan gerakan-gerakan mesianis. Teologi harmoni sebagaimana dipikirkan BIRA IV ini lebih bersifat praksis. Jadi berbeda dengan teologi universal (Swidler, W.C. Smith) dan ekumenis (Hans Küng) yang lebih mengedepankan penggarapan teologi sistematis. Dasar pertimbangan biblis-teologis dari teologi harmoni dikatakan BIRA IV berasal dari Misteri Tritunggal Mahakudus yang merupakan komunitas harmonis, yaitu Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Disebutkan pula bagaimana Allah telah menciptakan semuanya baik adanya dan indah serta harmonis. Teladan hidup dan ajaran Kristus juga menampilkan sikap-sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni. Kerajaan Allah merupakan realitas yang menampilkan harmoni.38 Tindakan Roh Kudus yang menyatu-padukan bangsa-bangsa dari berbagai bahasa dan suku dalam peristiwa Pentekosta juga menunjukkan contoh keselarasan (Kis 2:1-12). 37 Penjelasan ini didasarkan atas "Final Statement of the Tenth and Eleventh Bishops' Institute on the Theology of Dialogue", BIRA IV/ 10&11, di Sukabumi, Indonesia, Juli 1988; Albert Poulet-Mathis, "Concern and Initiatives of the Federation of Asian Bishops' Conference", dalam Ecumenical and Interreligious Dialogue in Asia, no 7, 1990, hal. 63-93; Archbishop Angelo Fernandes, "Summons to Dialogue", dalam FABC Papers No.34, hal.5-40; "Theses on Interreligious Dialogue", dalam FABC Papers No.48, hlm 1-26; R. Hardawiryana, "Peranan Gereja Dalam Masyarakat Pluri-Religius di Asia", dan J.B. Banawiratma, "Wujud Baru Hidup Menggereja: Dialogal dan Transformatif", keduanya dalam Orientasi Baru, no. 5, 1991, hal. 9-13 dan 14-46. 38 Lih. R. Hardawiryana SJ., "Peranan Gereja dalam Masyarakat Pluri-Religius di Asia", dalam Orientasi Baru, no. 5, 1991, hal. 2732. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana dialog dalam perspektif Kerajaan Allah dipikirkan dalam Gereja Asia: bahwa dialog tidak berpusatkan pada Gereja, melainkan Kerajaan Allah. 22 Bagaimana teologi harmoni ini dijabarkan dalam praksis? BIRA IV dengan inspirasi dari rekomendasi sidang-sidang sebelumnya (terutama sidang gabungan antara Federation of Asian Bishops' Conferences dan Christian Conference of Asia di Singapore, tgl. 5-10 Juli 1987) melontarkan gagasan-gagasan: - Ekologi (kemiskinan Asia disadari sebagai langsung akibat dari alpanya perhatian terhadap keseimbangan alam; kerusakan alam sudah demikian mengkawatirkan), penghargaan terhadap martabat manusia (konsep dialog hanya menjadi mungkin ketika martabat manusia adalah bagian pertama dari kesadaran komunikatifnya), pembelaan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia terutama kelompok-kelompok minoritas (minoritas hampir di segala tempat dan jaman menjadi korban; di sini minoritas tak hanya dalam jumlah tetapi juga suara politik), menggalang dialog dan keselarasan antarumat beragama siapa saja (ketika pluralitas merupakan realitas hidup sehari-hari, aktivitas dialogal adalah kepenuhan hidup), pembangunan masyarakat dalam arti seutuhnya39 (dialog pada intinya mengejar keutuhan tata hidup bersama). Didesaknya memperhatikan keseimbangan alam, sebab keselarasan hubungan antarpribadi manusia harus pula mengalir dalam tindakan menjaga kelestarian alam. Keselarasan itu harus tercermin dalam penghormatan terhadap alam. Harmoni tidak dapat direduksi pada sekedar penampakan luar yang selaras, stabil, seragam. Harmoni justru mengandaikan kebalikannya, pluralitas. Harmoni mencakup pengalaman mendasar manusia. Harmoni menuntut keterlibatan seluruh pribadi manusia meliputi perasaan, akal budi, dan hatinya. Itulah sebabnya dialog interreligius tidak dapat hanya menyentuh sharing ajaran agama, melainkan juga pengalaman iman yang mendalam. Maksudnya juga pengalaman hidup keseharian dalam ruang lingkup alamnya. Teologi dialog, dalam konteks BIRA IV, dengan demikian pertama-tama bukan merupakan sistematisasi doktrin teologis, melainkan hubungan antarpribadi manusia dalam hidup, kerjasama, dan sharing kehidupan. Dari beberapa pengertian teologi dialog di atas kiranya jelas bahwa beriman Kristen pada akhirnya harus merupakan suatu refleksi yang tak terpisah dari pengalaman hidup sehari-hari. Dari pergaulan hidup dengan umat agama-agama lain. Dalam era pluralisme, hubungan dengan agama-agama lain tidak boleh dipandang sebagai sekedar sampingan “bila perlu”, melainkan diterima sebagai yang meneguhkan. Menantang. Mengembangkan. Menciptakan perdamaian. Mentransformasikan. Dengan teologi dialog, penghayatan iman menjadi lebih merangkul dan menyambut perbedaan. Harmoni, perdamaian, tata keadilan, dan tata dunia baru sebagai bentuk kehadiran Kerajaan Allah adalah cita-cita dan pengharapan. 3. PERGULATAN BUDAYA 39. Mengenai dialog diwujudkan dalam praksis pembangunan masyarakat diuraikan pula oleh Hardawiryana, lih. Ibid., 36-39. 23 Dialog budaya Apakah “budaya”? “Budaya” dalam bahasa Latin, “cultura” (Inggris “culture”), memiliki akar kata colere yang artinya mengolah (dalam makna seperti mengolah tanah). Akar kata Bahasa Latin ini membantu kita untuk memiliki gambaran bahwa “budaya” memang merupakan sebuah aktivitas mengolah kehidupan. Dalam makna ini, benarlah bahwa padi, jagung, palawija adalah hasil-hasil kreativitas manusia dalam mengolah tanah. Dan, cara kita mengolah tanah (yang pada tahapan berikutnya menjadi pondasi kehidupan sehari-hari) kita sebut sebagai budaya. Dari sini, budaya lantas mendapat kristalisasi makna sebagai “cara hidup sehari-hari”, “cara berpikir”, “cara mengelola kebersamaan”, “cara makan”, dan seterusnya. Pada tataran antropologis, “budaya” lantas diukir dalam artefak-artefak hasil seni, sastra, kerajinan tangan, pengolahan sawah, sistem kekeluargaan, sistem kekerabatan, sistem kekuasaan, sistem hak waris, sistem memberi nama, sistem penghitungan waktu, sistem irigasi, sistem komunikasi, bahasa, etika “unggah-ungguh”, dan seterusnya. Budaya tidak pernah tiba-tiba jadi. Budaya adalah cetusan dari kecerdasan akal budi, akal budi masyarakat. “Wayang”, misalnya, jelas merupakan produk dari kecerdasan manusia. Sebagai sebuah produk budaya, wayang memiliki sejarah luar biasa panjangnya. Wayang menjadi cermin kehidupan. Tetapi, tidak hanya itu, wayang adalah juga cetusan keindahan, sastra, musik gamelan, seni suara, seni lukis, seni keterpaduan dalam kebersamaan, seni cerita, drama, dan keseluruhan dari yang kita sebut keindahan. Dialog budaya, pada level makna ini, juga mengatakan dialog keindahan dari kehidupan sehari-hari atau everyday life. Istilah everyday life digulirkan oleh seorang filosof, bernama Edmund Husserl (seorang filosof Yahudi yang menderita hebat karena penindasan Hitler). Apakah everyday life? Hidup sehari-hari adalah realitas itu sendiri. Tidak perlu didefinisikan. Dalam hidup sehari-hari, orang berjumpa dengan sesamanya. Perjumpaan selalu memiliki bekas pengalaman. Ada sesama di pinggir jalan (atau di tengah jalan) yang memintaminta. Pada pengalaman ini, dalam hidup sehari-hari ada kesusahan. Pada momen lain, dalam hidup sehari-hari kita berjumpa dengan sesama yang lagi menghadapi situasi sakit berat karena kanker atau flu H1N1. Dalam hal ini sehari-hari identik dengan kecemasan dan ketidakpastian. Kita mendengar bahwa kasus lumpur Lapindo di SP3-kan (dihentikan). Kasus penyidikan perkara Lapindo berhenti, tetapi lumpur terus mengalir seiring dengan penderitaan para korban yang tidak menentu. Di sini everyday life tidak jauh berbeda dengan ketidak-adilan dan kehancuran norma-norma kehidupan. Tentu saja, juga ada perjumpaan yang menyenangkan hari ini, terutama dengan kawan lama dan pacar. Keseharian lantas juga memberikan kemungkinan tawa dan harapan. Jadi, kebudayaan bukan semata artefak seni, seni tari, seni lukis, seni suara, seni gamelan. Tetapi, kebudayaan adalah pengalaman hidup sehari-hari yang penuh dengan perkara-perkara nyata, duka, kecemasan dan harapan. Implikasi dari pengertian ini: mendialogkan kebudayaan tidak semata mendialogkan warisan artefak budaya-budaya masa lalu, tetapi mempercakapkan kehidupan sehari-hari. Almarhum Mbah Surip dan WS Rendra konon dipandang penting peranannya dalam budaya karena pada masa muda dan perjalanan hidupnya mereka menyumbang bahasa-bahasa yang 24 kritis terhadap hidup sehari-hari bangsanya. Di samping kritis, mereka juga berani “bermimpi” dan mengalami segala konsekuensi dari mimpi-mimpinya. Dialog yang sejati, saya pikir, juga adalah dialog tentang mimpi-mimpi kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, equal. Saya memaknainya secara tegas, itu berarti kita diajak untuk berdialog mengenai pahit getir, kecemasan dan kedukaan, tawa dan tangis hidup sehari-hari. Aktivitas ini memiliki beberapa konsekuensi demikian, menurut saya: Tidaklah cukup sebagai orang Katolik, saya hanya berdoa, ke Gereja, melakukan pujipujian dan menyembah Allah di dalam kapel-kapel. Tidaklah cukup beragama, menjalankan ibadah-ibadah agama saja. Mengapa tidak cukup? Sebab agama kait mengait dengan budaya, pengalaman keseharian hidup kita. Budaya adalah keseharian. Dalam iman Katolik, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak tinggal di angkasa raya, langit tinggi. Melainkan, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, Allah – sebagaimana ditunjukkan oleh PuteraNya – memilih tempat-tempat yang kumuh, kotor, becek, lusuh, miskin, bahu busuk dan seterusnya. Sehingga Allah tampak sebagai Allah yang “kalah”, dan bukan pemenang jaya. Menyembah Allah yang kalah Allah itu mahakuasa justru ketika Dia tidak ada, kalah. – Jean-Luc Marion Paradigma teologi dewasa ini bergeser dari perspektif Allah yang transenden dan imanen kepada Allah yang bergumul dalam kehidupan nyata. Allah adalah Pribadi yang terlibat dalam kerasnya perjuangan manusia. Teologi tidak lagi diasalkan dari aktivitas membayang-bayangkan eksistensi Allah yang hebat, tetapi dari refleksi “tanah terjal” (rough ground), konteks hidup manusia, yang juga konteks kehadiran Allah. Tampaknya janggal, Allah itu tidak ada. Tetapi, kejanggalan segera lenyap ketika diingatkan bahwa beriman pertama-tama sangat mengandaikan kesadaran keseharian hidup. Dalam keseharian, wajah Allah tidak kita jumpai. TanganNya tidak kelihatan. Bahkan kehebatanNya tersembunyi. Simak bagaimana aneka bencana dan kemalangan telah seakan “menenggelamkan” kehadiran Allah. Kita seakan sulit menghayati Allah yang hadir dengan segala kekuatanNya untuk melindungi manusia dari kemalangan. Jika Allah disebut not being, itu bukan penyangkalan eksistensiNya. Melainkan, manusia diingatkan akan keberadaannya, akan kebebasannya (Jean-Luc Marion, God Without Being, Chicago: Univ. of Chicago press, 1991). Allah sebagai not being identik dengan Allah yang tak berdaya, yang kalah. Ketika Allah kalah, manusia diuji, berjuang, memeluk keterbatasannya, memaknainya sebagai sarana penyembahan kepada Allah. Bagi Marion, cinta adalah wujud absolut dan indah relasi manusia dengan Allah. Tetapi bukan cinta seperti dalam banyak doktrin. Cinta itu manusiawi, sehari-hari. Cinta memiliki lapisan-lapisan tanpa batas, tanpa tingkatan, bahkan tanpa gradasi mutu. “Ketika kita melukiskan cinta kepada Allah dalam kalimat-kalimat ilusif indah”, tegas Marion, “saat itu pula cinta membuat kita terasing dari Allah sendiri.” 25 Allah solider Vinsensius a Paulo dan Teresa dari Calcuta, mistikus-mistikus pelayan orang miskin, keduanya menghayati bahwa Allah tinggal bersama manusia-manusia miskin, rapuh, tak berdaya, kalah dalam pertarungan kehidupan. Allah bukan Dia yang hebat. Allah tidak duduk di tempat tinggi, tetapi tinggal dalam gubuk-gubuk reot, di “koloni-koloni” kusta terpinggirkan, di tempat-tempat bencana, di bilik-bilik penjara, di trotoar-trotoar jalanan, dan di kampungkampung kumuh. Mengenai cinta, Vinsensius dan Teresa tidak memiliki rujukan lain kecuali pada Kristus sendiri. Teologi cinta mereka adalah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Allah hadir, menyapa, solider dengan manusia. “Sepuluh kali kita mengunjungi orang miskin dalam sehari, sepuluh kali itu pula kita berjumpa dengan Allah”, kata Vinsensius. Mencintai manusia yang miskin, malang, dan menderita berarti identik dengan mencintai Allah. Dengan begitu, Allah adalah Sang Cinta itu sendiri, karena Dia membiarkan diriNya berada dalam keterbatasan sebagaimana kodrat manusia terbatas adanya. Dalam Injil Matius 25:34 dst., Allah adalah “Raja” yang tidak mengasingkan diri, melainkan tinggal dalam “saudara-saudari-Nya yang paling miskin, menderita, dan hina”. Allah tampak tidak berdaya dalam kemiskinannya. Allah kalah Allah yang kalah tampil dramatis dalam kisah penderitaan Kristus. Yesus Kristus dalam pengadilan dijatuhi hukuman mati. Hukuman paling rendah konteks waktu itu adalah hukuman salib (bukan penggal kepala). Salib dengan demikian adalah lambang sekaligus realitas penghinaan serendah-rendahnya martabat manusia. Hanya penjahat kelas kakap yang disalibkan. Yesus digiring ke penyaliban setelah menjalani siksaan berat. Sampai-sampai Dia tidak sanggup memikul kayu salibNya sendiri. Sesampainya di atas bukit, kedua kakiNya dipaku, kedua tanganNya direntangkan, ditancapkan pada kayu yang menyilang. Dia disalib bersama dengan dua pencuri. Yesus berada di antara kedua penjahat yang dihinakan. Allah benar-benar kalah. Kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia – dalam Injil Markus 15:39 – dikatakan sendiri oleh mulut kepala pasukan: “Dia benar-benar Putera Allah.” Ungkapan itu justru dikatakan pada saat Yesus terkulai di atas kayu salib. Seruan itu malah muncul dari seorang yang tidak beriman kala melihat Tuhan yang kalah. Ada paradigma kontras luar biasa di sini. Yesus terkulai lemas tergantung di palang kayu, tetapi justru Dia kelihatan sebagai Allah. Yesus tidak berdaya, tetapi malah momen itulah yang menjadi bukti bahwa kehadiran Allah tampak nyata. Yesus mati, tetapi itulah awal kehidupan sejati. Yesus kalah, tetapi itulah bukti kemenanganNya paling absolut atas maut. Bagi teolog Karl Rahner menghayati kemenangan Kristus berarti menghadirkan kisah pilu kesengsaraan serta kematianNya di Salib. Paskah adalah kekalahan sekaligus kemenangan. Ke-Allah-an Kristus tidak terletak pada kedigdayaanNya, melainkan justru pada ketidakberdayaanNya. Ke-Allah-an Kristus justru terletak pada kemanusiaannya, pada solidaritasNya 26 (dengan derita manusia), pada bilur-bilur lukaNya (yang habis tuntas sampai pada kematianNya), keterkulaianNya (di atas Salib penghinaan). Kisah ketidakberdayaan Kristus bukan kisah masa lalu. Kisah kekalahan Kristus adalah representasi aneka kisah penderitaan dan kengenasan manusia-manusia zaman ini. Yesus disesah. Disalib. Dianiaya. Persis seperti manusia zaman ini juga teraniaya. Dihancurkan oleh kebencian satu sama lain (Israel & Hamas). Diberondong senapan liar (Mumbai). Dibom bunuh diri (Pakistan, Afganistan, Irak, Srilanka). Dirudal secara brutal (Gaza & sekitarnya). Dihempaskan bencana keteledoran dan kelalaian (Situ Gintung, banjir di kota dan kampungkampung kita). Didera ketidakadilan (para korban lumpur). Dicampakkan krisis finansial global (para buruh terkena PHK). Dihajar oleh ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dan keadilan (para korban Lumpur Lapindo/Porong). Dilumatkan oleh kegilaan sebagian orang dengan bombom di Kuningan Jakarta dan di tempat-tempat lain). Allah luar biasa, justru karena Dia memasuki wilayah aneka kisah duka “tanah terjal” hidup manusia. Tetapi, seperti Kristus ditinggikan dalam salib, demikian derita manusia tidak sia-sia. Tuhan tidak dipuji dalam kemenangan. Tidak juga dalam kemegahan. Tetapi, Dia sangat berkenan pada manusia-manusia yang berduka, luka. Dia hadir, menyapa, tidak meninggalkan mereka. Sebab, Tuhan sendiri telah kalah, tidak berdaya. Ghebre Mikhael Seminary CM Octave Easter 2010.