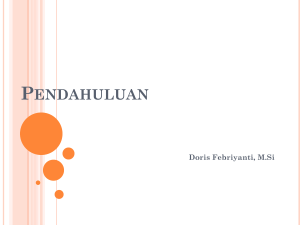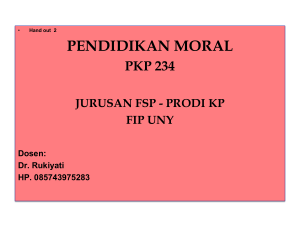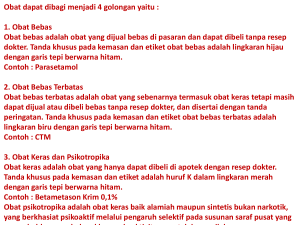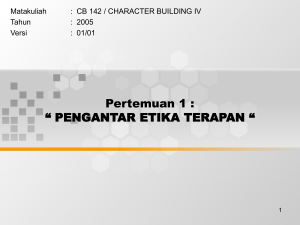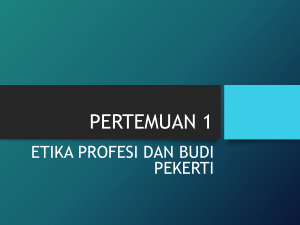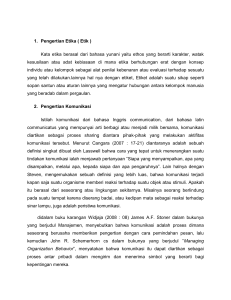etika
advertisement

ETIKA (MK-061) UK Maranatha BAG I. PENDAHULUAN: Proses belajar di Perguruan Tinggi paling sedikit bisa membawa dua perubahan pada diri mahasiswa. Pertama, tentu saja, Perguruan Tinggi memberi kepada mahasiswanya pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu (keahlian dan metodologi khusus bidang studi). Kedua, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, mau tidak mau, mahasiswa dibentuk ke arah tertentu (profil sebagai seorang akademisi). Pemberian mata kuliah etika dimaksudkan untuk membantu pada hal kedua itu, yaitu membantu mahasiswa mengintegrasikan pengalaman-pengalaman barunya yang didapati sebagai mahasiswa (terlibat dalam bidang keahlian khusus, iklim intelektual dan rasional, kontak dengan berbagai pandangan dan nilai) ke dalam kepribadiannya, sehingga tercapai kematangan dalam penilaian-penilaiannya. Jadi etika membantu mahasiswa dalam memberi penilaian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Jadi fungsi mata kuliah Etika di Perguruan Tinggi memang bukan untuk membangun sikap-sikap moral baru, melainkan terbatas pada segi integritas intelektual: membantu mahasiswa agar ia, sebagai mahluk yang berfikir secara rasional, dapat mempertanggung-jawabkan sikapnya terhadap pengalaman-pengalaman barunya itu. Pengertian Etika Etika berasal dari kata Yunani “Ethos”. Dalam bentuk tunggal, kata “ethos” berarti: Tempat tinggal; padang rumput; kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak “ta etha”, berarti: adat atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar BI: "Etika” mempunyai 3 arti: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral (akhlak). 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Dalam arti yang pertama, etika difahami sebagai ilmu atau filsafat yang mempelajari moral. Disini etika dibedakan dari moral. Sedangkan dalam arti yang kedua dan ketiga pengertian etika disamakan dengan moral. Sehubungan dengan tujuan dan fungsi mata kuliah etika di Perguruan Tinggi, maka dalam perkuliahan ini, kata etika dipahami lebih seperti pengertian yang pertama: Etika adalah ilmu atau filsafat, atau pemikiran kritis dan mendasar, yang mempelajari ajaran moral. Disamping kata etika, ada dua kata yang berhubungan namun mempunyai arti yang spesifik, yaitu Ethos dan Etis. Kata ethos dipakai untuk menunjuk sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan nilai seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya kata “ethos kerja” menunjuk pada sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan nilai seseorang atau sekelompok orang terhadap kegiatan bekerja. Sedangkan kata Etis dipakai untuk menunjuk suatu tindakan yang dilakukan, apakah sesuai atau tidak dengan tanggungjawab moral. Misalnya kalimat “Perbuatannya tidak etis”, berarti perbuatan dimaksud bertentangan dengan ajaran moral. Pengertian Moral Moral berasal dari bahasa Latin “Mos” (dalam bentuk jamak “Mores”), yang juga berarti kebiasaan atau adat. Kata “Moral” dipakai untuk menunjuk pada ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Bentuk moral yaitu: nasehat, aturan, wejangan, dan berbagai ajaran dari tradisi, adat, agama atau ideologi yang menilai suatu tindakan itu: benar atau salah, baik atau buruk, mulia atau jahat, luhur atau berdosa. Dalam Bahasa Indonesia, ada dua kata yang berhubungan dengan moral, yaitu: Amoral dan immoral. Amoral berarti perbuatan yang tidak berhubungan dengan konteks moral. Perbuatan yang bersifat nonmoral (netral) misalnya: berjalan, bermain bola, menonton televisi. Perbuatan-perbuatan itu tidak mempunyai nilai benar atau salah, baik atau buruk, mulia atau berdosa. Sedangkan kata immoral berarti perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, misalnya: membunuh, berzinah, memfitnah. Yang perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kata amoral sering diartikan sebagai immoral (perbuatan ang bertentangan dengan moral). Karena itu, pengertian yang benar akan kedua kata ini menjadi penting. 1 Pelajaran Etika bukan Pelajaran Moral! Ajaran moral secara sederhana bisa dikatakan adalah ajaran tentang "Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan, atau apa yang dilarang dan apa yang wajib kita perbuat". Dengan tujuan, agar kita menjadi manusia yang baik. Ajaran moral biasanya diberikan oleh orang yang berwewenang, misalnya guru, orang-tua, pemuka agama, dan pemuka masyarakat. Bentuknya, bisa berupa nasehat, wejangan, ajaran, peraturan, khotbah dan sebagainya (lisan atau tertulis). Sumber moral adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama atau idiologi. Etika tidak mengajar apa yang wajib dilakukan orang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral. Etika adalah ilmu, bukan ajaran. Jadi ajaran moral jelas berbeda dengan etika, walaupun keduanya saling berhubungan. Ajaran moral langsung formatif bagi manusia, sedang pelajaran etika secara langsung hanya menyampaikan suatu kecakapan teoritis. Ajaran moral ibarat buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan mesin dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi mesin itu sendiri. Ajaran Moral laksana petunjuk perjalanan, sedang etika laksana petanya. Etika membuat kita mengerti mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Dengan kata lain, etika merupakan cara kita untuk memperoleh orientasi kritis terhadap barbagai ajaran moral yang diberikan. Ajaran moral tidak diberikan di Perguruan Tinggi karena tidak banyak berguna, alasannya: 1. Pembentukan sikap-sikap moral adalah kejadian dialogis yang sebagian besar sudah selesai dalam tahun-tahun pertama hidup seseorang (masa kanak-kanak). Sehingga tidak banyak gunanya upaya membentuk sikap-sikap moral di Perguruan Tinggi. 2. Adanya pengandaian yang mengajar harus lebih maju dari yang diajar. Untuk etika (bidang teoritis) pengandaian ini bisa dibenarkan, yaitu: dosen yang mengajar etika lebih memahami ilmu etika dari pada mahasiswa yang diajarnya. Tetapi untuk moralitas, pengandaian itu belum tentu bisa dibenarkan, karena belum tentu moralitas dosen yang mengajar lebih baik dari moralitas mahasiswanya. 3. Pelajaran moral hanya bisa membuat mahasiswa menjadi sinis, jika tidak sesuai dengan prilaku dosendosen di kampus. (Cara terbaik mengajarkan moral kepada mahasiswa adalah dengan keteladanan prilaku para dosen, bukan dengan memberi kuliah yang berisi ajaran atau nasehat semata). Tujuan Pelajaran etika. Tujuan pelajaran etika adalah membuat mahasiswa menjadi lebih kritis. Kritis terhadap segala macam lembaga normatif: 1. Dirinya sendiri. (Membantu mahasiswa untuk menyadari bahwa ia berhak bahkan wajib untuk selalu mengikuti suara hati, bahwa ia tidak perlu begitu saja tunduk pada tuntutan pihak lain apapun juga). 2. Lembaga masyarakat: Keluarga, sekolah, lembaga agama, negara, dan lain-lain. (Terhadap lembagalembaga itu, etika mengajukan pertanyaan 1. Tentang legitimasi lembaga itu untuk membebankan kewajiban-kewajiban pada seseorang dan 2. Apakah kewajiban yang dibebankan itu dapat dipertanggung-jawabkan. Mahasiswa dengan demikian mendapat kecakapan intelektual untuk membebaskan diri dari sikap yes-man yang hanya membebek saja terhadap apa yang diajukan oleh pihak lain). 3. Segala macam idiologi: Baik yang terbuka, seperti idiologi negara, partai dan sebagainya. Maupun yang terselubung, seperti konsumtif, kemajuan, modernisasi dll, (Sering pihak yang mau memperkuat kedudukan, mematikan kritik dan memakai nilai masyarakat yang sejati untuk kepentingan mereka. Nilai sejati seperti Pancasila, musyawarah, kekeluargaan, disalahgunakan untuk melarang sikap tertentu yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan penguasa. Terhadap hal seperti itu, etika dapat membuat mahasiswa menjadi kritis). Etika juga bisa membantu mahasiswa memahami makna tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat (juga dalam bidang keahliannya), sehingga mampu bersikap terhadapnya. Dengan demikian ia tidak akan cepat puas dengan apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan keahliannya atau sekedar memenuhi tuntutan orang yang membayarnya. Etika dan Agama: Etika tidak mengantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Etika bahkan diperlukan oleh agama karena: 2 1. Orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia ingin mengerti mengapa Tuhan “memerintahkan” ia berbuat itu. Dalam hal ini, etika berfungsi memberi penjelasan rasional terhadap berbagai ajaran dan anjuran agama. 2. Seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu agama mengijinkan interpretasi yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Dalam hal ini, etika bermanfaat untuk memperoleh orientasi kritis terhadap berbagai penafsiran wahyu agama. 3. Bagaimanapun agama harus bersikap terhadap masalah-masalah moral yang dihadapinya pada saat ini, sekalipun hal itu tidak dibicarakan dalam wahyunya atau kitab sucinya, mis: masalah bayi tabung atau “clonning”. Dalam hal ini, etika bisa membantu agama untuk memperoleh orientasi kritis terhadap masalah yang dihadapi, sehingga agama bisa menentukan sikapnya secara bijaksana. 4. Etika memungkinkan dialog moral antar agama dan pandangan-pandangan dunia. BAG II. MANUSIA, PRILAKU DAN NORMA-NORMA Etika adalah ilmu yang mempelajari moral. Dan moral adalah ajaran-ajaran berlaku hanya pada manusia (Dalam dunia binatang tidak ada moral). Oleh sebab itu, pembicaraan etika dimulai dengan memahami ciri khas manusia. Salah satu ciri yang membedakan manusia dari hewan adalah: Manusia merupakan mahluk yang bertanya. Manusia tidak menerima secara pasif keadaan dirinya maupun lingkungannya. Manusia bukan saja ingin tahu segala hal yang ada di lingkungannya, tetapi manusia bahkan juga ingin tahu apakah ia bisa mengubah lingkungannya. Jika ternyata lingkungannya tidak bisa diubah, manusia akan berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu. Ada tiga pertanyaan dasar pada manusia. Pertanyaan pertama yaitu: apa? Dengan pertanyaan ini, manusia ingin tahu tentang segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan ditemukan dalam hidupnya. Misalnya, melihat fenomena jatuhnya titik-titik air dari langit, manusia bertanya: Apa itu? Lalu manusia memberi nama pada fenomena itu sebagai: hujan. Semua benda yang hidup maupun mati, yang ditemui oleh manusia, lalu diberi nama, yang menandakan pengetahuan dan pengenalan manusia pada benda atau fenomena yang dijumpainya. Pertanyaan yang kedua: mengapa? Pertanyaan ini diajukan, karena manusia tidak puas hanya sekedar tahu keberadaan lingkungannya. Manusia tidak berhenti dengan menandai dan memberi nama segala hal yang ditemukan. Manusia ingin lebih tahu, mengapa hal itu ada atau mengapa fenomena itu terjadi. Manusia tidak berhenti dengan menamakan hujan, tetapi ingin tahu juga mengapa terjadi hujan. Untuk itu, manusia mencari penjelasan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan menjelaskan, maka muncul pertanyaan ketiga pada manusia: bagaimana seharusnya? Mengetahui mengapa terjadi hujan, maka manusia bertanya: apa yang harus saya lakukan jika terjadi hujan? Untuk ini, manusia mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang harus dilakukannya. (Bagaimana memanfaatkan hujan bagi hidupnya, atau bagaimana menghindari hujan agar tidak menganggu hidupnya). Berbagai fenomena kehidupan dan berbagai kejadian serta situasi yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya yang kompleks, melahirkan banyak sekali pertanyaan tentang: bagaimana seharusnya ia bersikap? Apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan supaya hidupnya bisa berjalan dengan baik. Maka pengalaman manusia dalam bersikap terhadap lingkungannya tersebut kemudian dikembangkan oleh manusia menjadi norma-norma yang mengukur berbagai tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia. Kata “Norma” berasal dari bahasa Latin, artinya: siku-siku, yaitu alat yang biasa dipakai oleh tukang kayu untuk mengukur sudut dari benda yang dibuatnya (mis: bangku, meja, kusen dsb) sehingga sudutnya itu terukur dengan tepat secara simetris. Kata norma kemudian berkembang menjadi kata yang menunjuk pada: aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai suatu tindakan. Norma Khusus dan Umum: Dalam mengukur sebuah tindakan, maka ada norma yang khusus dan ada yang umum. Norma khusus adalah norma yang berlaku dalam bidang atau situasi khusus saja, misalnya norma bahasa, aturan permainan, tata tertib kampus dan sebagainya. Norma Bahasa Indonesia misalnya, hanya berlaku untuk 3 menentukan apakah penggunaan Bahasa Indonesia itu benar atau salah. Tentu saja norma bahasa Indonesia tidak bisa dipakai untuk mengukur penggunaan bahasa yang lain. Demikian juga dengan aturan permainan bola yang mengukur tindakan apa yang benar hanya berlaku sepanjang permainan bola saja, dan ketika permainan usai, aturan itu tidak berlaku lagi. Norma umum, adalah norma yang berlaku dalam kehidupan manusia secara umum. Norma umum dipakai untuk mengukur tindakan manusia dalam segala situasi dan tempat. Norma Umum dikelompokkan ke dalam tiga ketagori: Etiket, Hukum, dan Moral. Etiket merupakan norma yang berhubungan dengan sopan-santun. Di Indonesia, orang yang sopan memberi dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Di banyak tempat, kesopanan ditunjukkan dengan memanggil orang lain melalui sebutan marga atau nama belakang. Hukum merupakan norma yang terkait dengan tata tertib umum. Di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi hukum, antara lain: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Adat dan lain-lain (undang-undang dan peraturan pemerintah). Anggota masyarakat yang baik tak pernah melanggar hukum! Moral merupakan norma yang digunakan menilai perilaku manusia sebagai manusia. Manusia yang bermoral tak akan mencuri, membunuh dan menghargai sesama manusia kendati antara mereka terdapat perbedaan. Sering dikatakan bahwa moral menjadi norma tertinggi yang tidak bisa takluk pada norma lain. Bahkan moral dapat digunakan untuk menilai norma lainnya. Hubungan dan keterkaitan ketiga norma umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Etiket dan Hukum: Etiket dan hukum sama sekali tidak mempunyai hubungan. Kalaupun ada, bisa disebut etiket sebagai hukum non-formal yang sangat longgar. Perbedaan etiket berbeda dengan hukum: 1. Etiket hanya berdasarkan kesepatan, sedangkan hukum diundangkan secara formal dan tegas. 2. Etiket tidak memiliki sanksi tegas. Sedangkan hukum jelas tuntutannya. Etiket dan Moral: Etiket dan moral memiliki kesamaan, yaitu: Pertama: Baik etiket maupun moral menyangkut prilaku manusia. Hewan tidak memerlukan etiket, apalagi moral. Kedua: baik etiket maupun moral mengatur tindakan manusia secara normatif, dengan ukurannya sendiri-sendiri. Perbedaan Etiket dan Moral: 1. Etiket menilai cara. Misalnya memberi sesuatu harus dengan tangan kanan. Sedangkan moral menilai perbuatan itu sendiri. Mencuri itu salah, baik pakai tangan kanan atau tangan kiri. 2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Sedangkan moral berlaku sepanjang hidup. Diketahui atau tidak oleh orang lain. 3. Etiket sangat relatif. Yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan, bisa tidak sopan dalam kebudayaan lain. Moral lebih bersifat universal. 4. Etiket menekankan segi lahiriah yang kelihatan di luar. Sedangkan moral menyangkut manusia dari segi dalamnya. Hukum dan Moral: Hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum ditentukan oleh moralnya. Sebaliknya moral membutuhkan hukum. Tanpa hukum, moral hanya akan ada di awang-awang. Misalnya: moral menghormati milik orang lain, bukan saja diatur dalam undang-undang pidana tentang mencuri atau korupsi, tetapi juga perlu undangundang hak cipta. Hukum dan moral tidak selalu sama. Apa yang dinilai hukum itu benar, belum tentu secara moral benar. Misalnya: politik apartheid. Perbedaan hukum dan moral: 1. Hukum ditulis atau disusun secara sistimatis sehingga memiliki kepastian yang jelas dan obyektif. Sedangkan moral lebih terbuka untuk diperbincangkan secara subyektif. 2. Hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah (legalitas). Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Hukum tidak memperhitungkan motivasi. 3. Hukum sebagian besar dapat dipaksakan dengan sanksi. Sedangkan moral tidak dipaksakan. Sanksi moral, hanya hati nurani (atau bagi orang beragama: penghakiman Tuhan). 4. Hukum berdasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Hukum adat harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Sedangkan moral tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat. Nilai moral tidak ditentukan dengan suara terbanyak. 4 BAG III. KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB Pada materi diatas kita sudah memahami bahwa hidup manusia dibatasi berbagai norma. Lalu ~ dengan tergesa-gesa ~ mungkin langsung dikatakan: Etika dan Moralitas ternyata hanya bersangkut paut dengan soal aturan atau kaidah-kaidah. Tetapi tunggu! Mestinya harus ada pertanyaan di balik pernyataan yang tergesa-gesa tadi. Pertanyaan yang dimaksud ialah: jika setiap individu dibatasi berbagai aturan, di mana dong letak kebebasan manusia? Apakah dengan adanya norma manusia tidak lagi mempunyai kebebasan? Dan kalaupun masih ada, seberapa besar? Bagaimana posisi kebebasan ketika harus berhadapan dengan norma-norma? Beberapa Pandangan Mengenai Kebebasan Tulisan-tulisan mengenai sejarah kehidupan suatu masyarakat umumnya berkisar pada kisah memperoleh kebebasan. Di Asia dan Afrika, kebebasan yang diperjuangkan terutama pada hal-hal yang bersifat politis dan ekonomi. Sedangkan di Eropa dan Amerika, di samping politik dan ekonomi, juga kebebasan dari ikatan spiritualitas. Sering diceritakan, upaya mewujudkan kebebasan selalu berhadapan dengan orangorang yang tidak menghendaki kebebasan (karena kebebasan dianggap dapat menghilangkan hak-hak istimewa). Kendati banyak pemutarbalikan, namun sejarah universal mengatakan bahwa kebebasan “lebih banyak” memenangi pertempuran. Tetapi apakah definisi kebebasan? Pertanyaan inilah yang agaknya sulit dijawab meski kebebasan selalu merupakan tema percakapan universal! Menurut Bertens, percakapan mengenai kebebasan sebenarnya lebih banyak berada di ruang penghayatan atau refleksi. Ketika seseorang melakukan kebebasan-nya, dia bahkan jarang berpikir bahwa yang sedang dilakukan merupakan bentuk kebebasan. Karena itu definisi kebebasan cenderung relatif bagi setiap orang alias sulit didefinisikan. Sama seperti ketika diminta mendefinisikan kata “waktu”, bukan main sulit kendati kita mengucapkan kata itu lebih dari 5 kali sehari. Menurut John Stuart Mill, kebebasan berada di antara hubungan “sebab~akibat”. Pasti ada alasan, mengapa manusia selalu memperjuangkan kebebasan. Sebaliknya, setiap kebebasan selalu mempunyai akibat. Mill kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada seorangpun yang benar-benar merasa bebas, begitu pula sebaliknya. Seorang filsuf Prancis bernama Albert Camus melihat kebebasan sebagai bagian dari krisis kemanusiaan. Di setiap sudut bumi, manusia berteriak lantang mengenai kebebasan, tetapi hal itu sulit terpenuhi karena manusia tenggelam dalam krisis. Krisis kemanusiaan kemudian menyeret kebebasan ke dalam dirinya. Misalnya ketika terjadi perang, bukankah yang diperjuangkan adalah kebebasan? Sebaliknya, bukankah perang merupakan krisis kemanusiaan? Itu artinya, ketika manusia berusaha memperjuangkan kebebasan, pada saat yang sama krisis kemanusiaan pasti sedang mengintai. Hampir senada dengan Camus, Erich Fromm mengatakan bahwa semakin berusaha meraih kehidupan modern, manusia makin dibelenggu oleh ketidak-bebasan. Fenomena kehidupan modern seperti liberalisme ekonomi, demokrasi politik, otonomi, globalisasi dan individualisme merupakan ungkapan kerinduan manusia terhadap kebebasan. Namun sayang, tema-tema barusan justru lebih cenderung mengingkari kebebasan manusia karena menempatkan diri dalam gagasan sentralisme. Amerika Serikat merasa diri sebagai satu-satunya negara paling demokratis hingga berhak mendikte dan mengajari negara lain tentang demokrasi. Begitu pula mengenai liberalisme. Penganut-penganut agama pun setali tiga uang, selalu merasa diri lebih superior dan lebih benar dari penganut agama lainnya. Padahal, seperti sering dikemukakan para pemikir postmodern bahwa masyarakat sebenarnya lebih suka “tanpa koordinasi”. Jadi, apa dan di mana kebebasan itu gerangan? 5 Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial Kebebasan pada hakikatnya dapat dibagi ke dalam dua kategori: Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial. Dalam ilmu Etika, kebebasan mencakup dua hal: Sikap dan Tindakan. [Sikap juga meliputi Pikiran (segi kognitif) dan Perasaan (segi afektif)] Kebebasan Eksistensial adalah kebebasan secara positif: yang terdapat dalam diri setiap manusia untuk menentukan sikap dan melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri (Kebebasan ini sering ditandai dengan kalimat pembuka “Bebas Untuk…”). Jika orang lapar, dia bebas untuk makan, sekaligus bebas untuk memilih makanan yang tidak basi (Kebebasan Fisik). Jika seseorang merasa khawatir, dia bebas untuk bernyanyi, sekaligus bebas untuk berpikir bahwa dia sebaiknya bernyanyi di kamar mandi supaya tak menganggu orang lain (Kebebasan Psikis). Jika orang merasa rendah diri, dia bebas untuk memilih suatu gaya hidup, sekaligus bebas untuk menilai bahwa dirinya cocok dengan gaya hidup tersebut (Kebebasan Normatif). Kebebasan Sosial merupakan kebebasan secara negatif: dimiliki dan dihayati dalam hubungannya dengan orang lain atau kebebasan yang dilakukan pada saat orang lain tidak dapat membatasinya. (Kebebasan ini sering ditandai dengan kalimat pembuka “Bebas Dari…”) Kendati dibedakan, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial pada dasarnya senantiasa beriringan. Hubungan kedua kebebasan tersebut terletak pada maknanya, yaitu bahwa kebebasan eksistensial maupun kebebasan sosial merupakan tanda dan ungkapan martabat manusia. Sehingga hal-hal yang terdapat dalam kebebasan eksistensial juga memperhitungkan kebebasan sosial. Batas-batas Kebebasan Setelah mengenal dua jenis kebebasan, kita disadarkan bahwa Etika ternyata menunjukkan banyak hal yang belum terpikirkan ketika manusia hanya berbicara tentang kaidah atau norma-norma. Namun kembali diingatkan, kebebasan selalu mempunyai batas meski batasan yang dimaksud tidak selalu terkait dengan norma. Faktor-faktor yang membatasi kebebasan manusia yang umum dikenal ada tiga: Faktor dari dalam diri, Faktor lingkungan dan Faktor regenerasi. Sebenarnya masih ada satu lagi: Faktor Determinisme. Bagaimana penjelasannya? 1. Faktor Dari Dalam Diri Manusia (Fisik, Psikis, Psikologis) Faktor yang pertama ini membatasi baik kebebasan eksistensial maupun kebebasan sosial. Misal-nya jika seseorang menyandang cacat (tuna netra), orang tersebut tidak bebas lagi menikmati indahnya pemandangan lereng Tangkubanperahu. Pada saat yang sama, cacat fisik juga membuat orang tersebut tidak lagi bebas mencalonkan diri sebagai presiden. Artinya, kebebasan sosial dia pun menjadi terhalang. Misalnya lagi, jika seseorang mempunyai gangguan psikis seperti IQ rendah atau keterbelakangan mental. Orang tersebut tentu tak bebas melakukan salah satu kebebasan eksistensial manusia yakni berpikir. Bahkan, banyak sekali jenis kebebasan sosial yang tidak dapat lagi dia nikmati. Contoh lainnya, jika seseorang mempunyai gangguan psikologis seperti suka mengutil (klepto). Kebebasan eksistensialnya pasti terganggu karena tidak mampu menyadari bahwa perilakunya mengganggu orang lain. Seorang kleptomania tidak bisa disamakan dengan pencuri biasa karena masalah kesadaran itu tadi. Sejajar dengan itu, kebebasan sosial seorang klepto otomatis terbatas. 2. Faktor Lingkungan (Alam, “Budaya” maupun Ekonomi) Faktor yang kedua ini juga membatasi kebebasan eksistensial dan sosial sekaligus. Masyarakat Indonesia misalnya tidak bebas menikmati bermain ski karena negeri ini tidak pernah mengalami musim salju. Begitu pula, orang-orang Nepal tidak bebas menikmati hasil-hasil laut karena negeri itu tidak mempunyai laut. Faktor “budaya” dapat dijelaskan melalui contoh ini: anak yang lahir dan bertumbuh di tengah keluarga pencuri profesional, kebebasan-nya menjadi anak yang baik dan jujur pasti terganggu. 6 Contoh-contoh faktor ekonomi yang membatasi kebebasan eksistensial dan sosial ialah anak-anak keluarga berpenghasilan rendah. Kebebasan mereka untuk memperoleh pendidikan yang tinggi pasti terbatas. Meski selalu diupayakan pemerintah, pencanangan biasanya teoretis saja. Begitu pula ketika mereka berupaya memperoleh jaminan pelayanan sosial. 3. Faktor Regenerasi Faktor yang ketiga ini juga menyentuh kebebasan eksistensial maupun kebebasan sosial. Yang menjadi taruhannya adalah masa depan umat manusia. Misalnya untuk mencegah bencana (banjir dan tanah longsor), kebebasan manusia memanfaatkan sumber daya alam harus dibatasi. Negara-negara yang penduduknya over membatasi kebebasan orang mempunyai anak banyak-banyaknya. Sebaliknya, di negara-negara yang penduduknya sangat jarang, kebebasan menikmati hidup tanpa anak-lah yang justru dibatasi. 4. Faktor Determinisme Dalam pengertian yang paling sederhana, determinisme ialah “hubungan dalam keterikatan yang menetap”, atau bisa juga disebut “kodrat”. Faktor Determinisme juga menciptakan pembatasan kebebasan sosial dan eksistensial. Terjadinya pembatasan kebebasan sosial, menurut logika determinisme, diakibatkan munculnya anteseden (= faktor-faktor yang mendahului). Misalnya jika saya mengajukan diri menjadi calon presiden dalam pemilu mendatang, sebenarnya saya sedang mengerjakan salah satu kebebasan sosial. Tetapi apakah pencalonan saya itu murni dari kehendak hati saya atau hanya karena saya didorong oleh teman-teman dari Partai Bantal Guling? Jika ternyata saya mencalonkan diri karena dipengaruhi orang lain, dapat dikatakan bahwa saya sebenarnya tidak bebas. Begitu sebaliknya, jika saya mencalonkan diri karena kehendak hati, patut dipertanyakan: dari manakah kehendak hati itu datang? Apakah karena saya berusaha melakukan balas dendam politik terhadap presiden sebelumnya? Atau, apakah saya ingin meraih kekuasaan semata-mata agar teman-teman dan saudara saya dapat berbuat semena-mena pada orang lain. Jika memang demikian, kebebasan sosial yang ingin saya raih berarti berasal dari suatu jenis “penyakit” psikologis. Faktor Determinisme sebenarnya cukup hangat dan ramai dibicarakan, terutama karena dapat dilihat dari (dan menghubungkan) beberapa disiplin ilmu sekaligus: ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, teologi dan pedagogi. Namun karena beberapa pertimbangan teknis institusional, faktor ini untuk sementara dapat dikesampingkan. Di luar pengenalan keempat faktor di atas, kiranya perlu juga dipertanyakan: mengapa selalu ada pembatasan, terutama terhadap kebebasan sosial? Jawaban yang disediakan Etika ada dua, yakni: 1. Karena hak kebebasan tiap-tiap individu pasti akan selalu berhadapan dengan hak kebebasan yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain (kebebasan versus kebebasan). Jadi supaya hak bebas tidak saling “tabrakan” maka kebebasan perlu dibatasi. 2. Karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tanpa keterlibatan berbagai pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat itu berhak membatasi kebebasan. Pertanyaannya kemudian, dengan cara apakah masyarakat boleh “seperlunya” membatasi kebebasan sosial setiap orang? Dalam pertemuan di kelas, cara-cara ini telah diungkapkan dengan memberi contoh: bagaimana cara mencegah seseorang masuk ke dalam private room kita? Jawab yang disediakan ada empat: Memaksa (mengunci pintu kamar) Mengancam / memanipulasi keadaan (menakut-nakuti dengan menambatkan seekor anjing) Mewajibkan / melarang (memperingatkan dengan menulis “Dilarang Masuk”) Mengkondisikan situasi Yang hendak ditekankan di sini, jika individu atau kelompok sosial bermaksud membatasi kebebasan pihak lain, maka perlu diperhitungkan supaya cara yang digunakan tetap menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang dapat menentukan sendiri sikap dan tindakannya. Cara-cara yang hormat tersebut sekaligus 7 bertujuan meletakkan tanggung jawab pada setiap orang yang hendak merealisasikan kebebasan-nya. Karena kebebasan akan selalu berhadapan dengan soal yang satu itu: Tanggung Jawab! Tanggung Jawab Untuk menyederhanakan istilah, definisi tanggung jawab yang digunakan pada kuliah ini: Jawaban yang harus dan bisa diberikan setiap orang tentang pelanggaran kebebasan yang dilakukan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan: 1. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan 2. Tanggung jawab berkaitan dengan “penyebab” (pelanggaran) Tanggung jawab Dalam Kebebasan Eksistensial: Telah disebutkan bahwa Kebebasan Eksistensial merupakan kebebasan milik setiap orang tanpa dipengaruhi kenyataan lain di luar dirinya. Dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab, kebebasan eksistensial tidak hanya berarti bahwa yang diputuskan seseorang tak boleh dibebankan pada orang lain, tetapi sikap dan tindakan yang dilakukan sendiri juga harus dipertanggungjawabkan. Karena sikap dan tindakan secara positif tidak berada di dalam ruang hampa dan pasti mempunyai pengaruh ke luar diri orang tersebut. Dengan kata lain, kebebasan eksistensial bukan berarti bahwa setiap orang boleh bersikap dan bertindak seenaknya, tetapi setiap orang diberi kebebasan untuk mengisi ruang kebebasannya masing-masing sehingga bermakna. Terhadap kebebasan sosial, tentu tak perlu dijelaskan lagi karena orang yang melakukan-nya sudah pasti harus bertanggungjawab karena berhubungan dengan orang lain. Beberapa Kategori Tanggung jawab Karena berkaitan dengan “penyebab”, maka tak pelak lagi, orang yang tak menyebabkan sesuatu terjadi tidak perlu bertanggungjawab. Artinya, tanggung jawab bersifat pribadi / individu. Jika teman Ratna menabrak seseorang di Jl. Surya Sumantri, Ratna tidak bertanggung jawab kendati teman tersebut menggunakan sepeda motor Ratna. Jika seorang ayah melakukan tindakan kriminal, istri dan anak-anak tidak bertanggung jawab dan tidak boleh disuruh ikut bertanggung jawab. Memang, di antara para ahli sepakat bahwa tanggung jawab bersifat kolektif juga dapat diajukan tetapi sangat tergantung pada persepsi orang mengenai status kolektifitas tersebut. Dengan begitu tanggung jawab kolektif masih diperdebatkan kesahihannya. Masih berkaitan dengan sifat personalitas di atas, tanggung jawab tentu bersifat langsung. Namun sering juga muncul tanggung jawab tidak langsung, terutama jika melekat pada masalah atau sifat-sifat struktural. Sejalan dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, tanggung jawab juga terbagi ke dalam retrospektif (atas perbuatan yang sudah berlangsung dan semua konsekuensinya) dan prospektif (atas perbuatan yang akan datang atau sikap yang berpengaruh kemudian). Menolak Bertanggung Jawab Lalu apa yang harus dikatakan jika individu menolak bertanggung jawab? Individu yang menolak bertanggung jawab sesungguhnya berada dalam situasi seperti ini: di satu pihak sadar tentang tanggung jawab dan memahami perbuatan yang sangat bernilai. Namun di pihak lain karena malas, tidak mau susah, takut, emosi, sentimen atau dikuasai nafsu, individu tersebut menolak bertanggung jawab atau lari dari apa yang sesungguhnya dia akui sebagai perbuatan yang luhur dan penting. Seperti seseorang yang sebenarnya sangat senang berada di puncak gunung tetapi karena tak mau bangun pagi, tak 8 tahan haus, enggan menghadapi cuaca dingin atau tidak berusaha melatih dirinya, maka ia tidak jadi naik dan tidak akan pernah sampai di puncak. Jadi menolak bertanggung jawab bukan membuat seseorang lebih bebas. Malah sebalik-nya, individu yang lari dari tanggung jawab adalah individu yang dipenjara oleh sifat-sifat malas, oleh emosi, oleh rasa sentimen atau oleh nafsu sehingga kebebasan eksistensial yang dia miliki justru memudar. Pendeknya, mereka yang tidak bertanggung jawab ialah oknum yang tidak kuat dan tidak mampu melakukan apa yang dinilainya sendiri sebagai yang paling baik. Dapat dikatakan, individu yang bertanggung jawab ialah yang mampu menguasai diri, yang tidak takluk oleh perasaan-perasaan dan emosi-emosinya, yang sanggup untuk menuju tujuan yang disadari sangat penting, meski sangat berat. Makin bertanggung jawab, pasti semakin bebas!!! BAG IV. CARA BERPIKIR ETIS Menyadari kebebasan dan tanggungjawab mendorong manusia untuk menentukan sikap secara etis. Akan tetapi, menentukan suatu tindakan, tidak sesederhana mengikuti suatu anjuran moral tertentu saja. Ada kompleksitas cara manusia berfikir, sebelum ia mengambil keputusan etisnya. Untuk menjelaskan beberapa cara berpikir etis, pertama-tama akan diuraikan sebuah analisis cerita Analisis Cerita Agus (siswa kelas 3 SMU) meminta ijin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke pesta ulang tahun seorang temannya. Ayah dan Ibu mengijinkan dengan satu syarat: Agus sudah harus kembali ke rumah sebelum jam 23.00 malam. Agus berjanji, lalu pergi. Tetapi apa yang terjadi? Agus baru kembali pukul 02.00 pagi. Alasan Agus: “Saya sebenarnya tidak ingin melanggar janji kepada ayah dan ibu. Tetapi saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Teman-teman tidak ada yang pulang di bawah jam 23.00. Waktu saya berniat pamit, temanteman menertawakan dan mengejek saya. Karena itu saya terpaksa batal pulang supaya tidak malu dan kehilangan muka di hadapan teman-teman. Semua baru sepakat pulang jam 00.30. Dan ternyata, ada dua orang teman cewek yang rumahnya di Jatinangor. Tidak ada angkot, dan cuma saya yang membawa mobil. Akhirnya saya harus bersedia mengantar Ellen dan Nita terlebih dulu karena, tahu kan, Jatinagor itu jauh. Saya mengaku bersalah…tapi saya tidak dapat berbuat lain!!! “ Jawaban Ayah: “Gus, saya memahami keadaanmu. Tetapi ketahuilah bahwa janji adalah janji! Janji harus ditepati! Apapun alasannya, kamu tetap bersalah dan karena itu tetap harus dihukum!” Tanggapan Ibu: “Jangan gitu dong, Pap! Aku tahu bahwa Agus bersalah. Ia bahkan sudah mengakuinya. Tetapi mengapa harus dihukum? Agus toh tidak berbuat kriminal. Malah ia melakukan tindakan yang baik, yakni mengantar teman-temannya perempuan pulang. Bukankah itu tindakan yang luhur?” Cerita sederhana di atas menampilkan tiga cara berpikir etis. Deontologis, Teleologis dan Kontekstual. DEONTOLOGIS Ayah berpikir dari sudut pandang “prinsip”, “hukum” atau “aturan”. Dalam sudut pandang seperti itu, orang yang selalu menjunjung tinggi prinsip, hukum atau aturan adalah Benar. Sebaliknya, orang yang tidak taat pada prinsip berarti Salah. Dan tidak boleh ada kompromi terhadap aturan. 9 Cara berpikir seperti ini disebut DEONTOLOGIS: mendasarkan diri pada prinsip hukum atau aturan obyektif yang berlaku mutlak dalam kondisi apapun, terhadap siapapun yang terikat pada aturan tersebut dan harus berlaku tegas. Kekuatan cara berpikir DEONTOLOGIS: Memberi pegangan yang jelas dan tegas terhadap suatu sikap dan tindakan Memberi peluang pada penyusunan kodifikasi hukum, aturan atau perundang-undangan. Sementara kelemahan cara berpikir ini adalah: Membuat daftar hukum makin panjang (aturan dibuat sedemikian detail) Membuat orang terjebak pada sikap legalisme yang kaku dan beku Cenderung tidak dinamis, sementara kehidupan manusia justru semakin kompleks dan terus berubah / berkembang Membentangkan adagium “Manusia adalah pelayan hukum” [Padahal seharusnya “Hukum adalah pelayan manusia]. Semboyan: “Tujuan yang Baik belum tentu Benar” TELEOLOGIS Ibu berpikir dari sudut pandang Tujuan. Dalam sudut pandang seperti itu orang cenderung lebih melihat tujuan sebagai tolok ukur. Sehingga tujuan yang baik patut dijunjung tinggi, sementara tujuan yang jahat patut dikesampingkan. Cara berpikir seperti ini disebut TELEOLOGIS: mendasarkan diri pada kategori tujuan (baik atau jahat). Meski “secara aturan” salah, tetapi apabila tujuannya baik, maka orang tersebut harus dianggap baik [ingat contoh hukum pertolongan di negara bagian Arkansas]. Sebaliknya, meski aturan diikuti, tetapi jika tujuannya jahat, maka orang tersebut harus dianggap jahat. Kekuatan cara berpikir TELEOLOGIS: Mengetahui pentingnya norma obyektif sebagai ukuran benar dan salah, tetapi tidak menganggap hal itu sebagai ukuran terakhir untuk menilai manusia. Sebab yang lebih penting adalah Tujuan dan Akibat. Menghindarkan orang dari penilaian bersifat legalisme yang kaku dan beku. Sementara kelemahan cara berpikir ini adalah: Sulitnya menentukan ukuran penilaian “baik” dan “jahat” Aristoteles pernah menjelaskan bahwa tujuan yang baik adalah yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apa ukuran obyektif “kebahagiaan”? John Stuart Mill juga pernah mengatakan bahwa tujuan yang baik adalah jika memberi kebaikan pada sebanyak mungkin orang “the greatest good for the graetest number”. Tapi seberapa banyak? Apakah jika menolong dua orang sudah dapat dikategorikan banyak? Dapat terjebak pada upaya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan Dan jika lebih banyak melihat “tujuan akhir”, dapat mengarahkan manusia pada hedonisme (kenikmatan sebagai tujuan akhir) Semboyan: “Cara yang Tidak Benar bisa saja mencapai Tujuan atau Hasil yang Baik” KONTEKSTUAL Agus tidak terlalu mempersoalkan apa yang Benar dan Baik, tetapi berpikir dari sudut pandang situasional. Cara berpikir seperti ini disebut KONTEKSTUAL: mendasarkan situasi / kondisi riil sebagai pertimbangan pokok sebelum mengeluarkan keputusan etis. Ukurannya Tepat atau Tidak Tepat. 10 Kekuatan cara berpikir KONTEKSTUAL: Lebih bebas memperhitungkan, menilai situasi dan mengambil keputusan Sementara kelemahan cara berpikir ini: Dapat terjebak pada pertimbangan yang relatif Penilaian terhadap situasi sangat subyektif Tidak mempunyai pegangan yang jelas dan tegas Dapat mengarahkan kehidupan manusia pada nihilisme. Ketiga cara berpikir tersebut dapat diikuti seluruhnya asal digunakan dengan hati-hati dan bijaksana. Ketiganya memiliki ukuran kebenaran ~ sekaligus keterbatasan masing-masing. Dan karena kehidupan manusia demikian kompleks, ujuaran seperti inilah yang terpenting: “pada akhirnya, setiap orang harus mengambil keputusannya masing-masing! Kalau bisa, keputusan yang muncul adalah yang Benar, Baik dan Tepat.” Mungkinkah hal itu selalu terwujud? REFLEKSI KRITIS Selain melalui cerita di atas, cara berpikir etis juga dapat diterangkan melalui refleksi kritis terhadap normanorma. Refleksi kritis pertama mengarah pada soal boleh tidaknya norma dilanggar atau diabaikan. Bolehkah norma-norma itu dilanggar? Dan jika boleh, alasan apa yang mendasari pelanggaran tersebut? Apakah individu yang melakukan pelanggaran norma masih tetap bisa dianggap sebagai orang baik? Refleksi kritis kedua mengarah pada pertanyaan situasional atau keadaan khusus (dengan segala keunikan dan kompleksitasnya) ketika norma-norma dijalankan. Refleksi kritis ketiga menyangkut kepentingan-kepentingan yang bersembunyi di balik rumusan setiap norma. Mengapa ajaran moral mengatakan demikian? Bukankah rumusan hukum tertentu mengandung kepentingan politik pemerintah? Adakah hubungan antara etiket dengan kepercayaan mitis tertentu? BAG V. PERAN HATI NURANI Dalam penjelasan sebelumnya telah dipetakan bahwa pertanyaan “bagaimana seharusnya” mendapatkan jawaban melalui dua hal: [1] Secara praktis, yaitu melalui norma yang dirumuskan bersama oleh setiap kelompok sosial. Bagaimana seharusnya? Dengar dan ikutilah ajaran moral! Bagaimana seharusnya? Jangan menyimpang dari penjelasan hukum! Bagaimana seharusnya? Lakukanlah menurut etiket! [2] Secara reflektif, yaitu menghubungkan dan mempertimbangkan pemberlakukan setiap norma pada situasi, aspek kebebasan manusia, persoalan tanggung jawab dan cara berpikir manusia yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya perlu disadari bahwa pertanyaan “bagaimana seharusnya” itu perlahan-lahan telah mengalami perubahan sifat menjadi sebuah tuntutan. Tututan demi tuntutan, dalam realitas tampak diajukan oleh lembaga-lembaga normatif seperti keluarga, negara, institusi-institusi sosial atau lembaga masyarakat, ideologi, bahkan agama dan ego. Mengapa ego termasuk dalam kategori lembaga normatif? Meski abstrak dan berbau psikologis, ego pada dasarnya bersifat umum pada setiap individu. Dengan ego itu pula tiap-tiap individu mengajukan tuntutantuntutan kepada pihak lain di luar dirinya, yang hampir seirama dengan tuntutan-tuntutan keluarga, masyarakat, negara, ideologi dan agama. Itulah sebabnya ilmu Etika mengkategorikan ego sebagai salah satu lembaga normatif. 11 Pada kenyataan yang lain, tuntutan-tuntutan lembaga normatif terhadap individu juga sering bertentangan dengan norma-norma yang tersedia atau sudah dikenal. Karena itu akan muncul situasi problematis. Tetapi lebih dari sekadar pertentangan antara norma dan tuntutan lembaga normatif, yang paling sering dan sulit dihadapi justru adalah tuntutan lembaga-lembaga normatif itu sendiri. Dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu menghendaki anaknya mengikuti jejak orang tua menjadi pejabat atau birokrat kendati sang anak tidak berminat. Negara menginginkan setiap warganya untuk tidak mengkritik pemerintah kendati kesalahan demi kesalah terkuak terus-menerus. Ideologi menekan tiap-tiap individu agar tidak menumpuk hasil kerjakerasnya karena fasilitas umum telah disediakan dan cukup berlimpah. Namun demikian, tuntutan demi tuntutan lembaga normatif tidak begitu saja dapat menghampiri setiap individu dan langsung mendapatkan respon karena setiap individu mempunyai kebebasan eksistensial yang kadang sulit dijangkau dan dijamah oleh lembaga-lembaga normatif. Individu tentu akan memberi respon terhadap setiap tuntutan seperti itu namun terlebih dulu mengalami proses rasionalisasi dan internalisasi etis dalam dirinya. Rasionalisasi dan internalisasi tersebut berlangsung dalam pikiran maupun perasaan setiap individu. Rasionalisasi dan internalisasi tuntutan lembaga-lembaga normatif tentu melibatkan kemampuan individu yang bersangkutan untuk memahami norma-norma yang muncul di sekitar tuntutan itu, memperhitungkan aspek kebebasan (eksistensial maupun sosial-nya) serta tanggung jawab, dan juga mempelajari situasi kondisi serta tujuan yang lebih baik dan menguntungkan ~ bagi dirinya maupun pihak lain yang ada di sekitarnya. Sampai pada akhirnya, individu yang bersangkutan mampu merumuskan suatu sikap atau jawaban etis mengenai tuntutan-tuntutan yang dialamatkan padanya. Sikap dan jawaban tersebut akan membentuk komitmen pribadi yang tidak dapat dioper atau diambil-alih oleh individu lain. Begitu pula dengan resiko (kecil maupun besar) yang mungkin dihadapi akibat sikap dan jawaban yang dihasilkan. Tetapi perlu ditegaskan, apapun sikap dan jawaban etis yang lahir dari setiap individu ~ setelah mengalami proses rasionalisasi dan internalisasi, seluruhnya akan dihayati, diuji dan disaksikan oleh hati nurani yang bersangkutan. Penghayatan dan pengujian hati nurani itulah yang berperan untuk membentuk komitmen (berkadar tinggi) pada setiap individu ketika merespon tuntutan lembagalembaga normatif. Dengan kata lain, hati nurani merupakan kesadaran moral setiap individu dalam situasi konkret. Hati nurani, dengan demikian, adalah pusat kemandirian setiap individu. Partai politik pemenang pemilu atau calon presiden paling populer sekalipun tidak mungkin mampu mengikat hati nurani orang lain. Sebaliknya, hati nurani sering menolak tuntutan-tuntutan lembaga normatif yang berlawanan. Seperti kata orang bijak, “Ikutilah kata nurani Saudara!”. Apakah hati nurani bersifat mutlak? Tentu saja. Kemutlakan hati nurani sesungguhnya terletak pada kemampuannya melawan prasyarat-prasayarat yang diajukan lembaga-lembaga normatif. Menguntungkan atau merugikan, populer atau dicemooh, enak atau pahit…seluruhnya tidak mempengaruhi hati nurani. Lalu, apakah dengan sifat kemutlakan yang seperti itu hati nurani selalu benar? Tentu tidak. Mengapa? Seperti telah diuraikan, sebelum hati nurani memunculkan suaranya (menguji dan menghayati sikap dan keputusan etis), terjadi sebuah proses yang dinamakan rasionalisasi dan internalisasi etis. Proses ini sesungguhnya melalui koridor penilaian dan pertimbangan yang cenderung cukup luas pada kebanyakan individu. Beberapa masukan dari pihak lain (ingat aspek cara berpikir!) ikut pula dijadikan bahan pertimbangan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pertimbangan dan penilaian bersifat manusiawi yang sangat besar selalu mendahului hati nurani. Dan pertimbangan serta penilaian manusiawi tentu tidak selalu 100% benar! 12 Karena itu ada beberapa “rekomendasi” ilmu Etika sehubungan dengan peran hati nurani terhadap sikap, keputusan atau jawaban etis. [1] Terbuka terhadap penilaian-penilaian (aspek cara berpikir) pihak lain mengenai masalah etis yang muncul [2] Berusaha mencari semua informasi yang berharga dan diperlukan demi memberi penilaian dan pertimbangan yang tepat [3] Mengasah hati nurani dengan selalu belajar memberi sebuah sikap atau keputusan etis [4] Memperhatikan legalitas moral pada setiap sikap atau keputusan etis yang muncul DAFTAR PUSTAKA 1. 2. 3. 4. K. Bertens, Etika (Jakarta, Gramedia 1997) K. Bertens, Perspektif Etika (Yogyakarta, Kanisius 2001) Frans Magnis Suseno, Etika Umum (Yogyakarta, Kanisius 1979) Frans magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta, Kanisius 1987) 5. Eka Darmaputera, Etika Sederhana Untuk Semua (Jakarta, BPK Gunung Mulia 1989) 6. James Rachels, Filsafat Moral (Yogayakarta, Kanisius 2004) 7. Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya (Yogyakarta, Kanisius 1992) 8. Hans Kung, Etik Global (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1999) 9. Robert Borong, Etika Bumi Baru (Jakarta, BPK Gunung Mulia 1999) 10. I Bambang Sugiharto, Wajah Baru Etika dan Agama (Yogyakarta, Kanisius 2000) 11. Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis Kumpulan karangan (Yogyakarta, Kanisius1992) 12. Supardan, Ilmu, Teknologi dan Etika (Jakarta, BPK Gunung Mulia 1991) 13