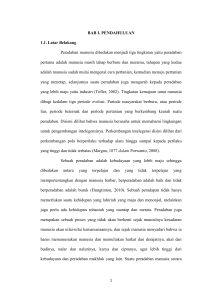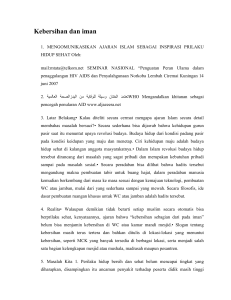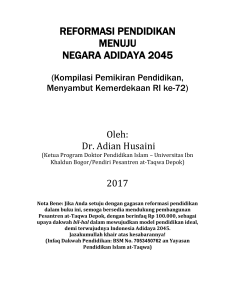sarana membentuk manusia beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia
advertisement

PENDIDIKAN: SARANA MEMBENTUK MANUSIA BERIMAN, BERTAQWA, DAN BERAKHLAK MULIA Oleh: Dr. Adian Husaini (Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor) “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Sungguh besar kemurkaan Allah jika kalian mengatakan apa yang kalian tidak mengamalkannya.” (QS 61:2-3). ***** Tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 20 tahun 2003, tentang Ssistem Pendidikan Nasional, sangatlah jelas: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga disebutkan, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan: (a). berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b). dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c). dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d). terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” ***** Begitulah tujuan pendidikan nasional di Indonesia, seperti tertulis secara resmi dalam Undang-undang. Jika dicermati, secara umum, tujuan itu sangat baik, yakni mencetak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Masalahnya, apakah dalam aplikasinya, tujuan itu benar-benar diwujudkan? Untuk mencapai tujuan pendidikan itulah maka diperlukan tiga unsur penting, yakni: guru/dosen, kurikulum, dan metode pembelajaran. Agar mencapai tujuan pendidikan, yakni membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, maka haruslah disusun kurikulum yang bisa mengantarkan anak didik kepada tujuannya. Logisnya, kurikulum itu harus bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT). Karena itu, adalah hal yang aneh, jika tujuan pendidikan untuk membentuk manusia beriman dan bertaqwa, tapi kurikulum pendidikannya justru “menolak” wahyu sebagai sumber ilmu. Contoh mudahnya, sebenarnya keliru dan janggal, mahasiswa Muslim di UI, ITB, IPB, UGM, Unair, ITS dan sebagainya, tidak diajarkan Ulumuddin secara memadai. Para mahasiswa Muslim tidak mempelajari Ulumul Quran, Ulumul Hadits, Ushul Fiqih, Bahasa Arab, Tarikh Islam, dan sebagainya. Ilmu-ilmu wahyu (revealed knowledge) itu dianggap bukan ilmu (knowledge) sebab tidak bersifat rasional dan empiris. Masih terjadi antara “ilmu umum” dan “ilmu agama”. Padahal, dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama sebenarnya merupakan model pendidikan warisan penjajah yang sudah out of date. Saat ini, di tingkat TK sampai SMA sudah banyak bermunculan Sekolah-sekolah Islam atau Pesantren Terpadu yang tidak lagi mendikotomikan antara ilmu-ilmu agama (ulumuddin) dan ilmu-ilmu rasionalempiris – yang dalam istilah sekarang disebut “ilmu-ilmu umum”. Kurikulum pendidikan yang masih memandang wahyu Allah bukan sebagai sumber ilmu adalah kurikulum sekuler yang seyogyanya tidak dipaksakan kepada mahasiswa Muslim. Konsep kurikulum dalam Islam mengintegrasikan antara ilmu-ilmu fardhu „ain dan ilmu-ilmu fardhu kifayah secara proporsional, sesuai dengan tujuan dan kemampuan pelajar/mahasiswa. Ilmu Fardhu „Ain adalah ilmu yang wajib dimiliki setiap Muslim, seperti ilmu aqidah Islam, ibadah wajib, dan sebagainya. Sedangkan ilmu Fardhu Kifayah adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh sebagian Muslim; tidak seluruhnya, seperti ilmu pengobatan, elektronika, tekbik bangunan, ilmu komputer, dan sebagainya. Misalnya, untuk anak-anak muslim super cerdas, bisa ditargetkan, sarjana lulusan UI, ITB, atau IPB, UGM,– minimal -- harus memahami aqidah Islam dan tantangan pemikiran kontemporer, menghafal al-Quran 10 juz, menguasai bahasa Arab dengan bauk, memahami dasar-dasar Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, dan sebagainya, ditambah dengan ilmu-ilmu empirisrasional, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, seperti matematika, fisika, statistika, jurnalistik, akuntansi, kedokteran hewan, ilmu gizi, arsitektur, dan sebagainya. Jadi, seharusnya, untuk mahasiswa Muslim, mereka bisa mendapatkan muatan kurikulum di Perguruan Tinggi dengan komposisi 50:50, yakni 50% ulumuddin (ilmu wahyu/revealed knowledge) dan 50% ilmu-ilmu rasional-empiris. Apakah ini mungkin? Jawabnya, sangat mungkin! Itu sudah banyak terbukti di tingkat SMA. Kini, tidak sulit menemukan lulusan SMA yang sudah hafal al-Quran, menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan baik, sekaligus juga menguasai mata pelajaran sains kontemporer. Sayangnya, setelah mereka memasuki Perguruan Tinggi Umum, “ilmu wahyu” mereka tidak berkembang; bahkan mungkin berangsur-angsur memudar, karena tidak mendapatkan media untuk pengembangannya. Karena itulah, sudah saatnya, Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki Pusat Studi Islam yang kuat. Di berbagai Universitas di Barat saja, sejak ratusan tahun lalu sudah dijumpai pusat-pusat studi Islam yang canggih, meskipun semua itu dibentuk untuk tujuan orientalisme secara umum. Hanya saja, salah satu masalah besar yang dihadapi di Indonesia adalah digunakannya “metode liberal” dalam Studi Islam. Yakni, metode pengkajian Islam a la orientalis, yang berselubung jargon “metode ilmiah” tetapi ujung-ujungnya menanamkan keraguan dan kebingungan terhadap kebenaran dari Allah serta menjauhkan mahasiswa dari pembentukan akhlak mulia. Model pendidikan ulumuddin metode orientalis itulah yang kini banyak dijumpai di Perguruan Tinggi. Yakni, pendidikan ulumuddin yang berselubung jargon ilmiah dan netral terhadap kebenaran. Metode semacam ini sangat meracuni pikiran, karena membuat seorang merasa benar dan bangga ketika ia tidak memihak antara yang haq dan yang bathil. Padahal, setiap Muslim dituntut untuk menegakkan amar ma‟ruf dan nahi munkar. **** Manusia beradab Dalam Islam, ada beberapa istilah yang identik maknanya dengan kata “pendidikan”, yaitu kata “tarbiyyah”, “ta‟lim”, dan “ta‟dib”. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas mengugkapkan, bahwa istilah “ta‟dib” lebih tepat untuk menggambarkan proses dan tujuan dari pendidikan dalam konsepsi Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang baik, yaitu manusia yang beradab. Itulah hakekat dari tujuan pendidikan, menurut Islam, yakni mencetak manusia yang baik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. S.M.Naquib al-Attas dalam bukunya, Islam and Secularism: “The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a goodman… the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab…” “Orang baik” atau good man, tentunya adalah manusia yang beradab; manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Tidak cukup seorang memiliki berbagai nilai keutamaan dalam dirinya, tetapi dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu, enggan menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar, dan suka mengumbar aurat dan maksiat. Lembaga Pendidikan Islam seyogyanya mampu melahirkan manusia yang beradab. Artinya, manusia yang mampu memandang dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah. Jika santri atau pelajar mempunyai potensi kecerdasan yang tinggi, dia harus diarahkan untuk menjadi orang yang „alim dan shalih sekaligus. Jika memang santri hanya memiliki kadar intelektual yang “pas-pasan”, maka dia harus tetap diarahkan dan dikembangkan potensinya menjadi orangorang yang baik, sesuai dengan potensi yang diberikan Allah kepadanya. Istilah adab juga merupakan salah satu istilah dasar dalam Islam. Para ulama telah banyak membahas makna adab dalam pandangan Islam. Istilah adab bisa ditemukan dalam sejumlah hadits Nabi saw. Misalnya, Anas r.a. meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: ”Akrimuu auladakum, wa-ahsinuu adabahum.” Artinya, muliakanlah anakanakmu dan perbaikilah adab mereka. (HR Ibn Majah). Sejumlah ulama juga menulis kitab terkait dengan adab, seperti al-Mawardi (w. 450 H), menulis Adab ad-Dunya wa ad-Din, Muhammad bin Sahnun at-Tanwukhi (w. 256 H) menulis Adab al-Mu‟allimin wa alMuta‟allimin, juga al-Khatib al-Baghdadi ( w. 463 H) menulis al-Jami‟ li-Akhlaq al-Rawi wa Adab as-Sami‟. Di Indonesia, K.H. M. Hasyim Asy‟ari, menulis sebuah buku berjudul Adabul „Aalim wal-Muta‟allim (edisi Indonesia: Etika Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007). Terjemahan harfiahnya: Adab Guru dan Murid. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang masalah adab. Kyai Hasyim Asy‟ari membuka kitabnya dengan mengutip hadits Rasulullah saw: “Haqqul waladi „alaa waalidihi an-yuhsina ismahu, wa yuhsina murdhi‟ahu, wa yuhsina adabahu.” (Hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik). Dikutip juga perkataan sejumlah ulama. Hasan al-Bashry misalnya, yang menyatakan: “In kaana al-rajulu la-yakhruja fii adabi nafsihi al-siniina tsumma siniina.” (Hendaknya seseorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun). Habib bin as-Syahid suatu ketika menasehati putranya: “Ishhabil fuqahaa-a wa ta‟allam minhum adabahum, fainna dzaalika ahabbu ilayya min katsiirin minal hadiitsi.” (Bergaullah engkau dengan para fuqaha serta pelajarilah adab mereka. Sesungguhnya yang demikian itu akan lebih aku cintai daripada banyak hadits.” Ruwaim juga pernah menasehati putranya: “Yaa bunayya ij‟al „ilmaka milhan wa adabaka daqiiqan.” (Wahai putraku, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu sebagai tepung). Ibn al-Mubarak menyatakan: “Nahnu ilaa qaliilin minal adabi ahwaja minnaa ilaa katsiirin mina ‟ilmi.” (Mempunyai adab meskipun sedikit lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu pengetahuan). Suatu ketika Imam Syafii pernah ditanya oleh seseorang: ”Sejauh manakah perhatianmu terhadap adab? Beliau menjawab: Setiap kali telingaku menyimak suatu pengajaran adab meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan ikut merasakan (mendengarnya) seolah-olah setiap organ itu memiliki alat pendengaran (telinga). Demikianlah perumpamaan hasrat dan kecintaanku terhadap pengajaran adab.” Beliau ditanya lagi, ”Lalu bagaimanakah usaha-usaha dalam mencari adab itu?” Beliau menjawab, ”Aku akan senantiasa mencarinya laksana usaha seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang.” ”Berdasarkan beberapa hadits Rasulullah saw dan keterangan para ulama di atas, kiranya tidak perlu kita ragukan lagi betapa luhurnya kedudukan adab di dalam ajaran agama Islam. Karena, tanpa adab dan perilaku yang terpuji maka apa pun amal ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah SWT (sebagai satu amal kebaikan), baik menyangkut amal qalbiyah (hati), badaniyah (badan), qauliyah (ucapan), maupun fi‟liyah (perbuatan). Dengan demikian, dapat kita maklumi bahwa salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah SWT adalah melalui sejauh mana aspek adab disertakan dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya.” (K.H. M. Hasyim Asy‟ari, Etika Pendidikan Islam (terj.), (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007). Demikianlah penjelasan KH Hasyim Asy‟ari tentang makna adab. Menyimak paparan ulama terkenal tentang adab tersebut, maka tidak bisa tidak, kata adab memang merupakan istilah yang khas maknanya dalam Islam. Adab terkait dengan iman dan ibadah dalam Islam. Adab bukan sekedar ”sopan santun”. Maka, tentunya sangat masuk akal jika orang Islam memahami kata adab dalam sila kedua itu sebagaimana dipahami oleh sumber-sumber ajaran Islam dan para ulama Islam. Sebab, memang itu istilah yang sangat khas dalam Islam. Jika adab hanya dimaknai sebagai ”sopan-santun”, maka bisa-bisa ada orang yang menyatakan, Nabi Ibrahim a.s. sebagai orang yang tidak beradab, karena berani menyatakan kepada ayahnya, ”Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata.” (QS 6:74). Bisa jadi, jika hanya berdasarkan sopan santun, tindakan mencegah kemunkaran (nahyu ‟anil munkar) akan dikatakan sebagai tindakan tidak beradab. Sebagian malah ada yang menganggap, menanyakan identitas agama pada seseorang dianggap tidak sopan. Banyak yang menganggap entang dosa zina, dan dianggap tidak etis jika masalah itu diangkat ke permukaan, sementara masalah korupsi harta bisa diangkat ke permukaan. Karena itulah, menurut Islam harkat dan martabat sesuatu adalah berdasarkan pada ketentuan Allah, dan bukan pada manusia. Sebagai contoh, kriteria orang yang mulia, menurut al-Quran adalah orang yang paling taqwa. (Inna akramakum ‟indallaahi atqaakum/QS 49:13). Maka, seharusnya, dalam masyarakat yang beradab, kaum Muslim harus menghormati seseorang karena keimanan dan ketaqwaannya. Bukan karena jabatannya, kekayaaannya, kecantikannya, atau popularitasnya. Itu baru namanya beradab, menurut alQuran. Begitu juga ketika al-Quran memuliakan orang yang berilmu (QS 35:28, 3:7, 58:11), maka sesuai konsep adab, seorang Muslim wajib memuliakan orang yang berilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan. Masyarakat yang beradab juga masyarakat yang menghargai aktivitas keilmuan. Tentu menjadi tidak beradab, jika aktivitas keilmuan dikecilkan, sementara aktivitas hiburan diagung-agungkan. Tidak mungkin suatu bangsa akan maju jika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya. Imam Syafii dalam sejumlah syairnya berkata: Wa‟lam bi-anna al-ilma laysa yanaaluhu, man hammuhu fi math‟amin aw malbasin. (Ketahuilah, ilmu itu tidak akan didapat oleh orang yang cita-cita hidupnya hanya untuk makanan dan pakaian); Falaw laa al-ilmu maa sa‟idat rijaalun, wa laa ‟urifa alhalaalu wa laa al-haraamu. (Andaikan tanpa ilmu, maka seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak dapat mengetahui mana halal dan mana haram). Umat Islam dan Bangsa Indonesia tidak mungkin akan menjadi umat dan bangsa besar jika mengabaikan tradisi ilmu ini. Jika budaya santai, budaya hedonis, budaya jalan pintas, terus dikembangkan, maka hanyalah mimpi saja untuk berangan-angan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang disegani dunia. Dalam perspektif Islam, manusia beradab haruslah yang menjadikan aktivitas keilmuan sebagai aktivitas utama mereka. Sebab soerang Muslim senantiasa berdoa: ”Rabbi zidniy ‟ilman” (Ya Allah, tambahkanlah ilmuku). Lebih dari itu, Rasulullah saw juga mengajarkan doa, agar ilmu yang dikejar dan dimiliki seorang Muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan ilmulah, maka manusia dapat meraih adab, sehingga dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai ketentuan Allah SWT. Inilah konsep adab sebagaimana dipahami oleh kaum Muslim. Sebagai pewaris nabi, para ulama diletakkan dan meletakkan dirinya di tempat yang terhormat. Para ulama inilah yang wajib memberikan keteladanan sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Al-Quran menyebutkan, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa (QS 49:13). Maka, seorang yang beradab tidak akan lebih menghormat kepada penguasa yang zalim ketimbang guru ngaji di kampung yang shalih. Dalam masyarakat yang beradab, seorang penghibur tidak akan lebih dihormati ketimbang pelajar yang alim dan shalih. Seorang pelacur atau pezina ditempatkan pada tempatnya, yang seharusnya tidak lebih tinggi martabatnya dibandingkan muslimahmuslimah yang shalihah. Itulah adab kepada sesama manusia. Adab juga terkait dengan ketauhidan, sebab adab kepada Allah mengharuskan seorang manusia tidak menserikatkan Allah dengan yang lain. Tindakan menyamakan alKhaliq dengan makhluk merupakan tindakan yang tidak beradab. Karena itulah, maka dalam al-Quran disebutkan, Allah murka kepada orang-orang yang mengangkat Nabi Isa a.s. sebagai Tuhan padahal, Nabi Isa adalah makhluk. Tauhid adalah konsep dasar bagi pembangunan manusia beradab. Menurut pandangan Islam, masyarakat beradab haruslah meletakkan al-Khaliq pada tempat-Nya sebagai al-Khaliq, jangan disamakan dengan makhluq. Itulah adab kepada Allah SWT. Nabi Muhammad saw adalah juga manusia. Tetapi, beliau berbeda dengan manusia lainnya, karena beliau adalah utusan Allah. Sesama manusia saja tidak diperlakukan sama. Seorang presiden dihormati, diberi pengawalan khusus, diberikan gaji yang lebih tinggi dari gaji guru ngaji, dan sering disanjung-sanjung, meskipun kadangkala keliru. Orang berebut untuk menjadi Presiden karena dianggap jika menjadi Presiden akan menjadi orang terhormat atau memiliki kekuasaan besar sehingga dapat melakukan perubahan. Sebagai konsekuensi adab kepada Allah, maka adab kepada Rasul-Nya, tentu saja adalah dengan cara menghormati, mencintai, dan menjadikan Sang Nabi saw sebagai suri tauladan kehidupan (uswah hasanah). Setelah beradab kepada Nabi Muhammad saw, maka adab berikutnya adalah adab kepada ulama. Ulama adalah pewaris nabi. Maka, kewajiban kaum Muslim adalah mengenai, siapa ulama yang benar-benar menjalankan amanah risalah, dan siapa ulama ”palsu” atau ”ulama jahat (ulama su‟). Ulama jahat harus dijauhi, sedangkan ulama yang baik harus dijadikan panutan dan dihormati sebagai ulama. Mereka tidak lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan para umara. Maka, sangatlah keliru jika seorang ulama merasa lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan penguasa. Adab adalah kemampuan dan kemauan untuk mengenali segala sesuatu sesuai dengan martabatnya. Ulama harusnya dihormati karena ilmunya dan ketaqwaannya, bukan karena kepintaran bicara, kepandaian menghibur, dan banyaknya pengikut. Maka, manusia beradab dalam pandangan Islam adalah yang mampu mengenali siapa ulama pewaris nabi dan siapa ulama yang palsu sehingga dia bisa meletakkan ulama sejati pada tempatnya sebagai tempat rujukan. Syekh Wan Ahmad al Fathani dari Pattani, Thailand Selatan, (1856-1908), dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin (Terj. Oleh Wan Shaghir Abdullah), berpesan agar seseorang mempunyai adab, maka ia harus selalu dekat dengan majelis ilmu. Syekh Wan Ahmad menyatakan : “Jadikan olehmu akan yang sekedudukan engkau itu (majelis) perhimpunan ilmu yang engkau muthalaah akan dia. Supaya mengambil guna engkau daripada segala adab dan hikmah.” Karena itulah, sudah sepatutnya dunia pendidikan kita sangat menekankan proses ta‟dib, sebuah proses pendidikan yang mengarahkan para siswanya menjadi orang-orang yang beradab. Sebab, jika adab hilang pada diri seseorang, maka akan mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan menuruti hawa nafsu yang merusak. Karena itu, adab mesti ditanamkan pada seluruh manusia dalam berbagai lapisan, pada murid, guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin bisnis, pemimpin masyarakat dan lainnya. Islam memandang kedudukan ilmu sangatlah penting, sebagai jalan mengenal Allah dan beribadah kepada-Nya. Ilmu juga satu-satunya jalan meraih adab. Orang yang berilmu (ulama) adalah pewaris nabi. Karena itu, dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang mecari ilmu dengan niat yang salah, untuk mencari keuntungan duniawi dan pujian manusia, sama saja dengan menghancurkan agama. Dalam kitabnya, Adabul „Alim wal-Muta‟allim, KH Hasyim Asy‟ari juga mengutip hadits Rasulullah saw: “Barangsiapa mencari ilmu bukan karena Allah atau ia mengharapkan selain keridhaan Allah Ta‟ala, maka bersiaplah dia mendapatkan tempat di neraka.” Karena begitu mulianya kedudukan ilmu dalam Islam, maka seorang yang beradab tidak akan menyia-nyiakan umurnya untuk menjauhi ilmu, atau mengejar ilmu yang tidak bermanfaat, atau salah niat dalam meraih ilmu. Sebab, akibatnya sangat fatal. Ia tidak akan pernah mengenal Allah, tidak akan pernah meraih kebahagiaan sejati. Lebih fatal lagi, jika manusia yang tidak beradab itu kemudian merasa tahu, padahal dia sebenarnya ia tidak tahu. Dalam pendidikan sains, adab harusnya meletakkan fenomena alam pada tempatnya, yakni sebagai “ayat-ayat Allah”. Alam semesta, termasuk tubuh manusia itu sendiri, bukan semata-mata objek pengamatan yang terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Karena itu, saat melakukan pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek, peneliti harus memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak terlepas dari Sunnatullah. Dengan sikap seperti itu, ia akan sampai pada kesadaran, “Rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilaa”. Dengan itu sang ilmuwan tidak akan bersikap sombong, tetapi bersikap tawadhu‟, karena meyakini, bahwa ilmu yang ia terima adalah merupakan karunia Allah. Begitu juga ia sadar bahwa di balik fenomena alam ini ada Dzat Yang Maha Kuasa yang mengatur alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Orang-orang yang gagal mencapai tujuan keilmuan ini, maka ia disamakan posisinya seperti binatang (QS 7:179). Inilah model pengajaran sains yang tidak memisahkan antara aspek fisika dengan metafisika; tidak membuang dimensi Ilahiyah dalam penelitian dan pengajaran; dan tidak “mengabaikan Tuhan” dalam pendidikan sains. Dengan cara seperti ini, seorang guru sains, juga sekaligus guru aqidah dan guru akhlak. Tidak memisah-misahkan antara pendidikan sains dengan pendidikan keimanan dan akhlak. Dengan cara seperti inilah, tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, bisa tercapai. InsyaAllah. (Bogor, 6 November 2013).