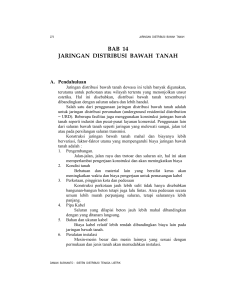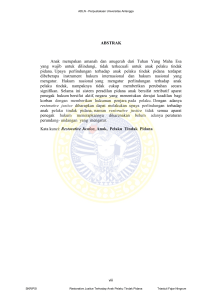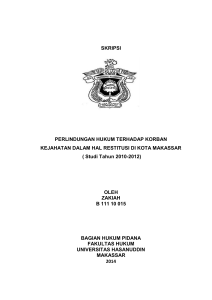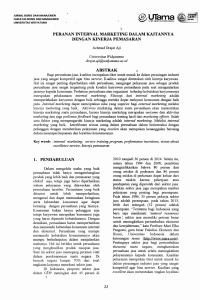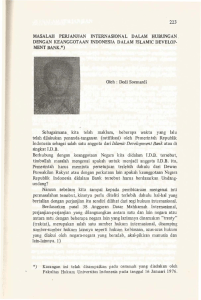buku jurnal 1 convert - Jurnal Hukum dan Peradilan
advertisement

Volume 02 Nomor ff+i'. '.i'F : iir.i..:ij:;:.. . :. . ': r ::'".. ffi ill""."' , l.l.t.'....: l I Morel 201 3 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan memuat naskah/artikel yang bersumber dari hasil penelitian/penelaahan tentang Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan. Jurnal Hukum dan Peradilan terbit tiga kali dalam setahun (Maret, Juli, Nopember) Penasehat Penasehat Penanggung Jawab Pemimpin Umum Wakil Pemimpim Umum Dewan Redaksi Pemimpin Redaksi Sekretaris Anggota Dewan Pakar Mitra Bestari Tata Usaha : 1. Dr. H.M. Hatta Ali, SH. MH. 2. Dr. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum. 3. Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. : Ny. Siti Nurdjanah, SH. MH. : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. : H. Amirullah Sholeh, SH. MM. : R. Wijaya Brata K, S.Kom. MM. : : Dr. Ismail Rumadan, MH. : Hudan Isnawan, SH., M.SI. : 1. Moch. Iqbal, SH. 2. Johanes Brata Wijaya, SH. 3. Budi Suhariyanto, SH., MH. 4. Mila Kurnia Rahma, SH. : 1. Dr. Andi Syamsu Alam, SH. MH. 2. Suwardi, SH. 3. Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. 4 Timur Manurung, SH., MH. 5. Widayatno Sastro Hardjono, SH., M.Sc. 6. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. : 1. Prof. Dr. Abdul Latif, SH. MH. 2. Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH. 3. Dr. Hasbi Hasan, SH. MH. 4. Dr. M. Fauzan Anshori, SH. MH. 5. Laksamana Muda A.R. Tampubolon, SH, MH. : Enny Yuniarti, S.Sos., Muchtar, SH, Sudaryanto, SH. MH., Auto, SH., Suhenda, SH. Alamat Redaksi : Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jln. Jend. A. Yani (By Pass) Kav. 58 Lt.10 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 13011 Email: [email protected] [email protected] Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 DAFTAR ISI Pengantar Redaksi Kebebasan Hakim dan Problematikanya dalam Sistem Peradilan Indonesia ……………………………………………… 1 Abdul Latif Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia : Refleksi dalam Penelitian Sosio-Legal ………………………….. 21 Herlambang P. Wiratman Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan ……………….. 35 Muhammad Djafar Saidi Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam ……………. 45 Asmuni Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum Nasional …….. 67 Dina Sunyowati Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ……………………………… 85 Muhammad Anis Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya) …………………………..……………………….. 109 Budi Suhariyanto Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht : Kajian Tentang Hak Atas Tanah oleh Penduduk …………………………………….. Harto Juwono 131 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 Biodata Penulis Pedoman Penulisan Jurnal Hukum dan Peradilan Ucapan terima kasih kepada Mitra Bestari ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 DARI REDAKSI Bisminllahirrahmannirrahim Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Segala atas segala, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, menuntun gerak dan memotivasi, memberi kemampuan berfikir kepada hambaNya untuk berbuat kearah yang terbaik, memberikan penghargaan yang tinggi kepada hamba-Nya yang selalu mengkaji berbagai problem kehidupan disekitarnya. Sebagai salah satu program prioritas Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI Penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan menjadi upaya positif yang dilakukan oleh Puslitbang MA-RI sebagai Supporting Unit Mahkamah Agung RI secara kelembagaan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Kehadiran Jurnal Hukum dan Peradilan ini diharapkan menjadi media bagi insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum dan peradilan untuk mengaktuasikan ide, pemikiran melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum dan peradilan secara ilmiah. Kehadirannya patut diapresiasi, dan diharapkan menjadi pencerah ditengah upaya besar bangsa menata pembangunan hukum dan peradilan masa mendatang. Beberapa tema yang menarik untuk dikaji dan diangkat dalam terbitan edisi perdana ini adalah: Kebebasan Hakim dan Problematikanya dalam Sistem Peradilan Indonesia, Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia: Refleksi dalam Penelitian Sosio-Legal, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia), Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya), Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht: Kajian tentang Hak Atas Tanah oleh Penduduk. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan seluruh unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah memberikan dukungan terbitnya jurnal ini, Juga Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI dan Kepala Puslitbang Kumdil MA-RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penerbitan jurnal ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi mengirimkan artikelnya,para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktunya untuknya mereview artikel para penulis, Semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jakarta, Maret 2013. Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Abdul Latif Kebebasan Hakim dan Problematikanya dalam Sistem Peradilan Indonesia Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No.1-21., hlm. Sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi karena ada peraturanperaturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan hams dipulihkan. Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya khususnya hukum materiil maupun formil. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan, namun kini belum optimal berfungsi untuk menyelesaikan administrasi peradilan seperti masih bertumpuknya putusan-putusan yang belum sampai kepada para pencari keadilan. Hak pencari keadilan untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak, diperlakukan sama dengan sesama pencari keadilan, serta memperoleh putusan dalam waktu yang wajar, sederhana dan biaya ringan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pencari keadilan. Perlu adanya peningkatan ke arah terjadinya pembahan atau pergeseran dari "hakim terikat" ke arah "hakim bebas", dan "keadilan menurut undangundang" ke arah "keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusannya, dari berfikir dengan mengacu kepada sistem ke arah berfikir dengan mengacu kepada masalahnya. Kata Kunci: Kebebasan hakim, Problematika, Sistem Peradilan Indonesia. Indonesian justice system is not fully functioning because there-rules and regulations that do not run as it should and there is a need to ensure greater freedom sanction judges in performing their duties. Public confidence in the judiciary should be restored. To strengthen the justice system needs to be guaranteed freedom of judges. Human resources need to be increased both its integrity and mastery of knowledge in particular substantive legal or formal. Modernization of the administration of justice would be better facilitate the course of justice will grow back confidence to the judiciary, but now is not optimal functioning to complete the administration of justice as is the accumulation of decisions that have not come to those seeking justice. Justice seeker the right to obtain justice freely and impartially, to be treated the same as fellow seekers of justice, and to obtain a decision within a reasonable, simple and low cost is a basic need for every seeker of justice. There needs to be increased in the direction of the change or shift from "the judge is bound" to the "independent judge", of "justice under the law" toward "justice according to the judge as set out in its decision, of thinking with reference to the system in the direction of thinking with reference to the problem. 2 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Keywords: Freedom of judges, Problems, Indonesian Justice System. Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Herlambang P. Wiratman Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia : Refleksi dalam Penelitian Sosio-Legal Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 22-34, hlm. Dalam dekade terakhir pasca Soeharto, Good Governance (GG) telah sering mendengar seperti 'mantra' GG tampaknya mudah diucapkan banyak bicara, formal, dan tumbuh menjadi cita-cita politik yang dominan serta konstitusional dan publik wacana administrasi besar yang telah berakar dalam hukum, kebijakan, dan pendidikan tinggi. Seperti ayam yang berkokok di pagi hari, is terns berbicara di pagi hari, lebar kotak bibit 'governance', seperti 'tata kelola kehutanan yang baik', 'tata kelola keuangan yang baik', 'good university governance', dan banyak lainnya. GG, dalam konteks itu, tampaknya seperti nutrisi yang tepat untuk mengatasi kelemahan sistem hukum Indonesia, birokrasi yang korup, dan kepemimpinan politik predatoric. Dalam hal ini, harus dilihat lebih dekat, apa yang sebenarnya keunggulan yang dimiliki saat GG adalah berbicara? Jelas, hukum adalah salah satu alat untuk memastikan pengoperasian mantra dalam pelaksanaannya, dan didasarkan pada penelitian utama yang dilakukan pada tahun 2005-2006, dengan fokus pada isu Reformasi Hukum dengan menerapkan pendekatan sosio-legal. Akibatnya, penelitian ini memberikan fakta yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan cita-cita bangunan politik atau diformalkan atau terwujud hukum dan kebijakan. Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa GG dalam konteks reformasi hukum di Indonesia sebenarnya sangat menakutkan dan melemahnya jaminan hak asasi manusia. Hukum, khususnya produk legislasi dan lembaga, serta transmisi mesin yang dominan dalam mengadvokasi pasar bebas (pasar reformasi hukum ramah gratis). Mungkin, kesimpulan tidak populer di tengah-tengah pidato ejaan bising GG dan proyekproyeknya. Namun demikian, Indonesia saat ini menunjukkan kelanjutan dari korupsi besar-besaran, pelanggaran HAM, impunitas dan semua situasi non-perlindungan dalam sistem hukum Indonesia. Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Reformasi Hukum, Pendekatan Sosio Legal In the last decade post Soeharto, Good Governance (GG) has been often heard like a `mantra'. GG seems easily uttered talkative, formalized, and grew into a dominant political ideals as well as major constitutional and public administration discourse which have rooted in law, policy, and higher education. Like a rooster crowing in the morning, he continued to speak out in the mornings, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 wide box spawn 'governance, such as 'good forestry governance, 'good financial governance, 'good university governance, and many others. GG, in that context, seems like an appropriate nutrition to overcome the weakness of the Indonesian legal system, corrupt bureaucracy, and the predatoric political leadership. In this regard, it should be viewed more closely, what is actually superiority owned when GG is talked? Obviously, the law is one of the tools to ensure the operation of the mantra in its implementation, and based on master research conducted in 20052006, focusing on the issue of the Law Reform by applying a socio-legal approach. As a result, this study gave the fact which is different or even contrary to the ideals of political buildings or formalized or materialized law and policy. For example, one study showed that the GG in the context of legal reform in Indonesia actually very sinister and weakening the guarantee of human rights. Law, especially product of legislation and institutions, as well as its machinery transmission are dominant in advocating free market (free market friendly legal reform). Perhaps, the conclusions is not popular in the middle of the noisy speech spelling of GG and its projects. However, Indonesia today shows the continuation of massive corruption, violation of human rights, impunity and all the non protection situation in the Indonesian legal system. Keywords : Good Governance, Law reform, Sosio Legal approach Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Muhammad Djafar Saidi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 35-44, hlm. Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya din sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Berhubung karena kaidah hukum dalam UUKUP memberikan wewenang luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak mewujudkannya. Oleh karena itu, kaidah hukum dalam UUKUP memerlukan penataan kembali untuk mencegah tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Korupsi, Perpajakan Implementation of the tax law in casu UUKUP aims to educate taxpayers fulfill their rights and duties, but tax officials and tax officials to enrich themselves abused in the form of committing corruption in the field of taxation. Since the rule of law because of the tremendous UUKUP authorizes the tax authorities that tax officials to make it happen. Therefore, the rule of law in UUKUP require realignment to prevent corruption in the field of taxation. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Keywords : Crime, Corruption, Taxation Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Asmuni Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 45-66, hlm. Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi atau daman. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina'iya.h untuk sebutan tanggung jawab pidana. Akan tetapi sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-qz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (baca: daman), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: `uqubah diyat, arusy dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. Daman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut daman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut daman `udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku. Kata Kunci : Ganti Rugi, Hukum Islam, Perspektif Hukum. The idea of daman towards both criminal and justice victims, from early time, has been mentioned in the nash of both Al-Quran and Al-Hadith. From the nash, Ulemas have formulated various fiqh forms concerning daman (compensation). In fact, from early time the Islamic Jurists have not applied the terms masuliyah madaniyah for justice responsibility, and masuliyah al ina'iyah for criminal one. However, several thinkers of classical Islamic law mainly al-Qurafi and al- `Iz Ibn Abdi Salam have introduced the term al-jawabir for justice conpensation (read: daman) and al-zawajir for criminal compensation (read: 'uqubah diyat, arus, etc.). Although in its development, up to recent time, Islamic Jurists often use the term masuliyah that is because of the Western work influences. Daman could occur because of deviation on akad (agreement) namely daman al-aqdi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 and could happen because of violation namely daman `udwan. In determining the compensation, the esential elements are darar or lost on the victims. Darar could occur on physical, material or things and service aspects; and it could also be on moral and emotional destruction or called darar adabi including name-reputation damage. The standard for the compensation either on quality or quantity must be similar to darar suffered by the victims. Although in certain cases, the multiplying compensation may happen based on the victims' condition. Keywords : Compensation Theory, Islamic Law, Law perspectives Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Dina Sunyowati Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum Nasional Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 67-84, hlm. Kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (pacta sunt servanda). Perjanjian internasional yang telah disepakati dan di sahkan dalam suatu ratifikasi oleh suatu negara, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua dan menjadi sumber hukum bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan. Hal ini berlaku juga di Indonesia. Setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang sudah tertuang dalam suatu persyaratan ratifikasi atau tidak, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sumber Hukum, Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional Countries agreement contained in an international agreement in the form of bilateral agreements, regional and multilateral agreements that are binding on the parties and a law for that entered into an agreement (pacta sunt servanda). International agreements that have been agreed and validated in a ratification by a country, then the agreement is valid and binding upon all be a source of law for the enforcement of law in making decisions. This is true also in Indonesia. Any international agreement that has been followed by Indonesia, which is contained in a ratification requirement or not, still have the force of binding for both parties. Keywords : International Law, Sources of Law, International Treaties, International Agreements. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Muhammad Anis Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Ketatanegaraan Indonesia Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 85-108, hlm. Negara dalam Sistem Selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan dan tentu kekurangan, di satu segi pembangunan insfrastruktur dan supra struktur berkembang secara pesat, namun perjalanan pemerintahan mengalami penurunan fungsi dan perannya bahkan stagnan. Oleh karena itu, terjadilah revormasi tahun 1998 dalam berbagai bidang. Sebagai jawaban menurunnya funsgi dan peran pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat lah pendapat dengan pembentukan organisasi barn di luar pemerintahan. Gagasan-gagsan tersebut diwujudkan dengan pembentukan komisi-komisi yang memerlukan anggaran Negara yang tidak sedikit, bahkan kadang-kadang terjadi benturan kewenangan antara komisikomisi juga dengan lembaga pemerintahan. Pembentukan komisi-komisi tersebut tidak lepas dari politik hukum. Kata Kunci : Politik Hukum Pelembagaan, Komisi Negara, Sistem ketatanegaraan During the 32 years of the New Order government certainly has its advantages and disadvantages, in terms of the development of infrastructure and suprastructure growing rapidly, but the journey has decreased function of government and its role even stagnant. Therefore, there was the Reform of 1998 in a variety of fields. In reply fungsi decline and the role of government under the Constitution of 1945, there was an opinion with the formation of a new organization outside the government. Gagsan ideas are realized with the establishment of committees that do not require the State budget a little, sometimes a clash of authority between committees also with government agencies. Committees should not be separated from the politics of law. Keywords : Institutionalization of Political Law, Commissions of the State, State Administration System Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Budi Suhariyanto Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya) Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 109-130, hlm. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Secara normatif, pengaturan restitusi dalam hukum positif masih belum tersinergikan dengan baik. Implikasinya, dalam hal penerapannya mengalami kendala berupa ketidaksingkronan struktur hukum. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu, ketidakharmonisan substansi hukum dan ketidaksingkronan struktur hukum ini hares segera dibenahi. Pembenahan fundamental dilakukan melalui Re-Filosofi pemidanaan dengan menjadikan restitusi sebagai pidana pokok dan memberikan posisi barn bagi korban dalam sistem peradilan pidana mendatang berdasarkan filsafat restoratifjustice. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Restitusi. Restitution is a form of legal protection form for victims of victim recovery oriented. Normatively, on the positive law, restitution has not been cooperated well yet. Consequenly, the application of the restitution had a problem, specifically unsynchronized legal structure. Under the integrated criminal justice system perspective, legal structure and legal substance disharmony need to be reorganized (regulated). A fundamental arrangement will be done by rephylosophy some punishment, than make restitution become a prinsipal (main)criminal and giving a new position for the victim to the later integrated criminal justice system based on the phylosophy of restoratifjustice. Key words: legal protection, victims, restitution. Kata kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dicopy tanpa izin dan biaya Harto Juwono Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht : Kajian Tentang Hak Atas Tanah oleh Penduduk Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 131-150, hlm. Pada saat ini, persoalan kepemilikian tanah diantara penduduk menjadi hal yang rumit dan sering mengakibatkan terjadinya konflik, baik individual maupun kelompok (massal). Adanya ketidakjelasan status tanah memerlukan suatu kajian dengan pendekatan historis atas pengaturan hukum atas tanah, yang berubah mengikuti rezim hukum, yang mengakibatkan perubahan pada hak dan status kepemilikan tanah tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah akibat ketidakjelasan dari pemerintah dalam menerangkan rezim hukum mana yang diberlakukan pada saat ini. Sebagian besar masyarakat masih bertahan dengan pemahaman tentang hak kepemilikan (bezitzrecht) atau hak penguasaan (beschikkingsrecht) atas tanah, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 yang berbeda dengan konsep hak milik atas tanah (eigendom). Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan konsep hak atas tanah (eigendom) dan hak-hal atas tanah lainnya yang diberlakukan pada saat ini sehingga tidak lagi terjadi konflik mengenai hak kepemilikan atas tanah. Kata Kunci : Hak Kepemilikan (bezitzrecht), Hak Kepemilikan Atas Tanah (eigendom), Sejarah Regulasi. Nowadays, land ownership's issues become complicated and often result in conflict to nation, either individually or groups (mass). Lack of clarity of the status of the land requires a historical approach to the study of the legal regulation of land that changed following regime, which resulted in changes to the rights and status of land ownership. Results of this study concluded that the problems came out from an incomprehensive notice from the regulator/government, in order to clarify which regime used by now. Most of the people are sticking with the understanding of property rights (bezitzrecht) or tenure (beschikkingsrecht) of land, which is different from the concept of land title rights (eigendom). Therefore, the Government is expected to socialize the concept of land title rights (eigendom) and other present land rights so the conflicts will decrease or subside. Keyword : property rights (bezitzrecht), land title rights (eigendom), regulation history KEBEBASAN HAKIM DAN PROBLEMATIKANYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA Abdul Latif1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Jl. Racing Centre Perum. Dosen UMI Blok G/3 Makassar Sul-Sel Abstrak Sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi karena ada peraturanperaturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan hams dipulihkan. Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya khususnya hukum materiil maupun formil. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan, namun kini belum optimal berfungsi untuk menyelesaikan administrasi peradilan seperti masih bertumpuknya putusan-putusan yang belum sampai kepada para pencari keadilan. Hak pencari keadilan untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak, diperlakukan sama dengan sesama pencari keadilan, serta memperoleh putusan dalam waktu yang wajar, sederhana dan biaya ringan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pencari keadilan. Perlu adanya peningkatan ke arah terjadinya pembahan atau pergeseran dari "hakim terikat" ke arah "hakim bebas", dan "keadilan menurut undangundang" ke arah "keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusannya, dari berfikir dengan mengacu kepada sistem ke arah berfikir dengan mengacu kepada masalahnya. Kata Kunci: Kebebasan hakim, Problematika, Sistem Peradilan Indonesia. Abstract Indonesian justice system is not fully functioning because there-rules and regulations that do not run as it should and there is a need to ensure greater freedom sanction judges in performing their duties. Public confidence in the judiciary should be restored. To strengthen the justice system needs to be guaranteed freedom of judges. Human resources need to be increased both its integrity and mastery of knowledge in particular substantive legal or formal. Modernization of the administration of justice would be better facilitate the course of justice will grow back confidence to the judiciary, but now is not 1 Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan kini Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 optimal functioning to complete the administration of justice as is the accumulation of decisions that have not come to those seeking justice. Justice seeker the right to obtain justice freely and impartially, to be treated the same as fellow seekers of justice, and to obtain a decision within a reasonable, simple and low cost is a basic need for every seeker of justice. There needs to be increased in the direction of the change or shift from "the judge is bound" to the "independent judge", of "justice under the law" toward "justice according to the judge as set out in its decision, of thinking with reference to the system in the direction of thinking with reference to the problem. Keywords: Freedom of judges, Problems, Indonesian Justice System. A. Pendahuluan Isu sentral tulisan ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah sistem peradilan Indonesia belum bebas dan mandiri, sehingga perlu ditelaah? Kalau kita bicara tentang "sistem peradilan" maka itu berarti bahwa sistem peradilannya belum bebas dan mandiri, tetapi perlu ditingkatkan agar bisa bebas dan mandiri. Di sinipun dapat timbul pertanyaan, apakah benar bahwa sistem peradilan Indonesia belum bebas dan mandiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu diketahui dan didiskusikan antara lain hal-hal yang berkaitan dengan problematika sistem peradilan, asas peradilan cepat dan lambannya peradilan, peran peradilan dalam mempositifkan hukum, penemuan hukum dan perubahan sosial, dan hakim dalam pembentukan hukum yang akan menjadi sub pokok bahasan dalam uraian berikut. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yang tidak menghendaki adanya konflik di dalam sistem itu, dan kalau terjadi konflik maka konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut, namun akan dipecahkan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Demikian pula dengan sistem peradilan yang erat hubungannya dengan sistemsistem lain dalam sistem hukum nasional seperti diungkapkan Bagir Manan2, sehingga dalam menilai atau memantapkan sistem peradilan, kita tidak boleh lepas dari sistemsistem lain dalam sistem hukum nasional. Sistem peradilan itu tidak berdiri sendiri dan mengingat pula keadaan umum dewasa ini, maka tidak dapat terlalu diharapkan sepenuhnya hasil yang maksimal dari usaha pemantapan sistem peradilan ini, jika dalam pembentukan undang-undang misalnya, karena tidak terkoordinasi, karena tidak memperhatikan sistem lain dalam sistem hukum nasional, maka hasilnya tidak memuaskan, karena isinya ada yang bertentangan dengan undang-undang lain. 2 Bagir Manan,bahwa dalam kenyataan, walaupun tradisi common law bertolak dari kebebasan individual hakim, tetapi disertai pula kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Demikian pula sebaliknya, meskipun tradisi kontinental bertolak dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tetapi kebebasan hakim dipandang mutlak dan tidak terpisah dari kekuasaan kehakiman yang merdeka (makalah, 2012:3). 2 2 Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia Meskipun demikian keadaan peradilan kita sudah cukup mengkhawatirkan untuk hanya bertopang dagu bersikap pesimistis dan tidak berbuat apa-apa. Maka kita hams sangat arif dalam usaha kita memantapkan sistem peradilan kita dengan selalu memperhatikan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional. Kita hams berfikir dalam sistem dan tidak partial. Kebebasan hakim merupakan asas utama peradilan yang diatur dalam Undangundang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"3. Selanjutnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihakpihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Jadi hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta mengadili (bebas untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemukan hukumnya, bebas dalam mengambil keputusan) serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Namun, kenyataan tantangan independensi hakim selalu datang dari pihakpihak yang kurang memiliki kesadaran hukum4, yaitu pengaruh dari pihakpihak berperkara, pengaruh dari pihak kekuasaan, dan dari kerabat bahkan ancaman dari pemndang-undangan.Tantangan dari pihak berperkara yaitu pengaruh suap, tekanan psikhis berupa ancaman dan tekanan pisik misal, demonstrasi, sedangkan tantangan yang berasal dari penguasa atau pemerintah yaitu hak keuangan lembaga peradilan ada ketergantungan dengan lembaga lain, ada perasaan superior dari penguasa, dan ada ketergantungan pelaksanaan tugas dengan instansi lain. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah pengaruh kerabat yaitu hubungan keluarga, pertemanan dan hutang budi. Ancaman perundang-undangan yaitu adanya RUU perubahan UU MA yang sangat berpotensi melanggar independensi hakim, berakibat membunuh kreatifitas hakim karena ancaman pidana terhadap hakim yang melanggar undang-undang, hanya akan ada hakim yang legalistik. Menimbulkan ketakutan bagi hakim untuk membuat putusan, karena putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusuhan diancam pidana dan denda. Rancangan UU tersebut menurut Harifin A. Tumpa merupakan "Malaikatul Maut" bagi rokh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Inilah 3 4 Harifin A. Tumpa, Independensi hakim bukanlah hak istimewa daripada hakim, tetapi merupakan sesuatu yang melekat pada hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan pencari keadilan. Kemerdekaan hakim harus diartikan bebas dari tekanan fisik maupun psikhis, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bebas dari pengaruh siapapun (makalah, 2012:3). Ibid, h. 4-5. 3 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 semua yang dapat dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun ancaman tersebut tidak perlu dibatasi dalam undangundang karena pada prinsipnya kebebasan hakim bukan tanpa batas karena hakim tidak boleh melampaui batas kewenangannya, hakim hams menjaga kepastian hukum dan hakim hams menjaga konsistensi putusan. Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat di seluruh dunia yaitu The independence of the judiciary shall be guaranted by the state and enshrined in the constitution or the law of the country 5, adalah merupakan dambaan semua bangsa, kebebasan hakim ini tidaklah mutlak. Hal ini dapat dilihat secara makro dan mikro yaitu Secara makro kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya, dan secara mikro di Indonesia kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undangundang Dasar, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para pihak dalam semua perkara. B. PEMBAHASAN 1. Problematika Sistem Peradilan Hakim tidaklah bebas dengan pembatasan seperti yang diketengahkan dimuka. Tidak sedikit terjadi campur tangan dari pihak luar kekuasaan kehakiman. Campur tangan dari pihak ekstra yudisiil yang berupa tekanantekanan, provokasi, surat sakti dan sebagainya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, membuat hakim tidak tenang dalam menjalankan tugasnya. Jaminan ketenangan atau keamanan bagi hakim kiranya sangat diperlukan agar hakim sungguh-sungguh dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi pihak ekstra yudisiil berdasarkan hati nuraninya dan keyakinannya. Ia hams dijamin perlindungannya terhadap tekanan, ancaman atau teror. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai sanksi lebih lanjut terhadap campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. Larangan campur tangan tidak hanya berlaku bagi pihak di luar kekuasaan kehakiman saja, tetapi ketentuan larangan campur tangan itu kiranya juga berlaku bagi hakim, yang berarti bahwa hakim wajib menolak campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman. Jaminan berupa rumah, kendaraan atau gaji tinggi tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan menghadapi campur tangan pihak ekstra yudisiil. Larangan campur tangan saja kiranya belumlah cukup kalau tidak disertai dengan sanksi, terutama bagi hakim. Sanksi, terutama bagi hakim, dalam hal ini secara tidak langsung akan melindungi hakim terhadap campur tangan pihak luar kekuasaan kehakiman, karena is dapat berlindung di belakang sanksi, untuk menolak campur tangan. 5 4 Basic Principles On Independence of Judiciary (diadopsi oleh The Seventh United Nations Congress On The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders di Milan, 26 Agustus — 6 September 1985. Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia Kenyataan dapat juga terjadi, bahwa pribadi hakim yang bersangkutan memang sengaja mau "dicampuri" atau dipengaruhi (suap). Hal ini tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada hakim, karena peradilan merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak: hakim, panitera, pengacara, para pihak, jaksa. Kalau tidak ada yang menawarkan (para pencari keadilan, pengacara dan sebagainya) tidak akan terjadi suap, kecuali apabila hakim yang minta, itupun masih tergantung kepada yang dimintai mau atau tidak. Baik atas permintaan hakim maupun atas tawaran pihak lain, kalau hakim akhirnya mau menerimanya (disuap), kedua perbuatan itu merupakan perbuatan tercela Teringat pada ungkapan dari Sidney Smith yang sangat memprihatinkan mengingat keadaan sekarang, yang menyatakan bahwa6. Betapa besar dosa kita kalau hal ini nanti benar-benar terjadi. Ini menyangkut integritas hakim yang memerlukan peningkatan integritas sumber daya manusia, yang dapat berupa pendidikan, penataran, eksaminasi putusan, lebih selektif dalam pengangkatan, promosi, evaluasi dan mutasi hakim serta sanksi yang lebih berat dalam hal terjadi pelanggaran oleh hakim. Untuk meningkatkan integritas, kecuali apa yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya meningkatkan juga kewaspadaan, aktivitas pengawasan dan pengetahuan para pengawas (hakim pengawas) serta secara konsisten menindak setiap pelanggaran. Jangan terlalu gegabah menganggap suatu pelanggaran sebagai "hanya penyimpangan prosedur" saja. 2. Asas Peradilan Cepat dan Lambannya Peradilan Speedy administration of justice atau peradilan cepat selalu didambakan oleh setiap pencari keadilan. Pada umumnya setiap pencari keadilan menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas walaupun akhirnya dikalahkan dari pada pemeriksaan yang bertele-tele, tertunda-tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan juga perkaranya. Sudahlah wajar kalau para pencari keadilan menghendaki penyelesaian perkara yang cepat, kecuali ingin lekas tahu mengenai kepastian (hukum) hakhaknya dalam suatu perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak beaya dan waktu. Ada ungkapan yang berbunyi: justice delayed is justice denied. Asas peradilan cepat ini diatur dalam UndangUndang Kekuasaan Kehakiman . Banyak penyebab lambannya jalannya peradilan mengingat babwa sistem peradilan melibatkan banyak pihak: hakim, panitera, para pihak, pengacara, jaksa dan sebagainya. Hakim dapat menunda sidang karena pelbagai alasan, karena sakit gigi, atas permintaan para pihak, para pihak atau pengacaranya tidak datang tanpa pemberitahuan atau pengacaranya minta ditunda sidang dengan alasan ada sidang di tempat lain dan pada umumnya itu semuanya 6 Sidney Smith, Nations fall when judges are injust, because there is nothing which the multitude think worth defending, 6 5 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 hanyalah bertujuan untuk mengulur-ulur waktu saja, untuk "menunda eksekusi". Permohonan banding dan kasasi seringkali hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja. Barangkali tidak jauh dari kenyataan kalau dikatakan bahwa (di Indonesia) perkara perdata bukanlah perkara perdata kalau tidak banding. Banding dan kasasi memang merupakan upaya hukum memperoleh putusan yang lebih tinggi.Akan tetapi kalau setiap perkara (perdata) dimintakan banding berarti bahwa kesadaran menurun karena permohoman banding hanya digunakan untuk mengulur-ulur waktu saja, atau putusannya tidak memuaskan karena tidak bermutu. Dalam masalah banding di dalam praktek seringkali tidak ditepati peraturannya, terutama mengenai tenggang waktunya: ini sudah menyangkut penyimpangan prosedur. Kedua hal tersebut di atas hakim hams berani menegur pihak yang bersangkutan, pengacara atau jaksa dan peraturan tentang hukum acara hams lebih ketat dijalankan. Berlarut-Iarutnya jalannya peradilan karena sering ditunda-tunda dan juga proses permohonan banding yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengurangi kepercayaan para pencari keadilan kepada pengadilan. Untuk lebih memperlancar jalannya peradilan perlu kiranya diadakan pemutakhiran (memodernisasi) administrasi peradilan seperti komputerisasi putusan dan arsip, alat fotokopi dan sebagainya hal ini telah dilakukan Mahkamah Agung meskipun belum optimal dalam kenyataannya. Penyelesaian perkara (terutama yang kondemnatoir) tidak jarang yang tidal( tuntas. Tidak tuntasnya penyelesaian perkara disebabkan karena putusannya terlalu formal: yuridis formal tepat, tetapi tidak dapat dilaksanakan, misalnya adanya putusan kasasi MA yang tidak mencantumkan dalam amar putusan yang menyatakan terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, sehingga tidak bermanfaat terutama bagi yang berkepentingan. Putusan semacam ini jelas tidak akan memuaskan pihak terpidana atau dalam perkara perdata tidak akan memuaskan pihak yang dimenangkan karena kecuali tidak dapat melaksanakan putusannya is misalnya hams mengajukan gugatan lagi. Di samping itu tidak jarang pula suatu putusan tidak menyelesaikan perkara dengan tuntas, akan tetapi justm menimbulkan perkara baru,yang dapat merupakan penyebab di sini adalah kurangnya alat bukti dan atau kurangnya penguasaan hukum materiil dan hukum formil dari hakim yang bersangkutan. Di dalam hal ini hakim harus berani melakukan penemuan hukum yang bebas, penemuan hukum yang tidak hanya bersifat system oriented saja tetapi juga problem oriented. Hukum materiil dan hukum formil pada umumnya di dalam praktek orang mudah terjebak dalam rutinitas pekerjaan. Tidak terkecuali dengan hakim, sehingga akhimya yang dikuasai mengenai hukum materiil dan formil hanyalah itu-itu saja atau bahkan tidak menguasai, sehingga putusanputusannya sering tidak bermutu. Dalam menemukan hukumnya ajaran 6 Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia mengenai penemuan hukum sering diabaikan atau tidak tahu7, bahkan sering menyimpang dan sistem hukum. Sebagai contoh misalnya ada hakim yang minta agar akta notaris itu dilegalisasi. Pertimbangan dalam putusan sering terlalu langsung atau sumir. Selama ini untuk kepentingan itu telah diadakan lokakarya-lokakarya dan seminar-seminar nasional oleh Mahkamah Agung seperti yang diselenggarakan melalui Pusdiklat MA pada tanggal 18 Oktober 2012. Di samping lokakarya dan seminar tersebut perlu adanya refreshing atau penyegaran dalam bentuk pendidikan bagi hakim dan seluruh perangkat peradilan yang terintegrasi dalam satu sistem. 3. Peran Peradilan dalam Mempositifkan Hukum. Sekarang ini, dunia peradilan semakin banyak melepaskan diri dari legisme yang ketat. Hal ini tidak terjadi hanya dalam bidang hukum perdata, tetapi juga dalam bidang hukum pidana. Terutama setelah diterimanya "alasanalasan penghapus pidana" yang ada di luar undang-undang. Norma-norma yang bersifat ekstra legal semakin banyak turut menentukan, dan asas-asas yang bersifat jurisprudensi memainkan fungsi dan peran penting dalam pelaksanaan undangundang. Di sini kelihatan bahwa acara peradilan merupakan suatu fungsi yang esensial dalam mempositifkan hukum, karena itu dengan perkembangan seperti sekarang ini, maka diadakan suatu corak baru dalam dunia peradilan. Disadari pula bahwa tercipta corak baru dalam peradilan, yang keadaannya lain daripada dulu sewaktu peradilan yang mengutamakan melaksanakan undangundang dengan menerapkan sepenuhnya kepada kejadian-kejadian yang ada. Dewasa ini produk yang dihasilkan oleh acara merupakan input pihakpihak yang berkedudukan penting dan berfungsi dalam proses peradilan. Perbedaan dalam kekuasaan dan dapat ikut sertanya penegak hukum yang lain daripada hakim dalam hal-hal yang bersifat juridis, akan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan hasil peradilan itu sendiri. Perspektif sebagian besar pihak yang terkena dapat pula menguasai jalannya acara peradilan.8 Secara singkat dapat dikatakan bahwa acara peradilan mengambil alih kedudukan utama dengan menggeser kedudukan pembentuk undang-undang, maka, dengan demikian peradilan merupakan faktor pembaharu dari materi hukum secara keseluruhan. Khusus mengenai hukum pidana, para ahli dalam bidang yang lugs ini akan banyak berfungsi turut menentukan dan berperan dalam pembentukan hukum yang berkeadilan. Namun, satu hal yang hams kita perhatikan, seperti diketahui di negaranegara Anglo Saxion peradilan memang mempakan sumber hukum yang 7 8 Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Penemuan Hukum sebuah pengantar, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karena itu hams dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. atau dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas, (2001:26). Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, (1984: 57). 7 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 pertama dan selanjutnya pula yang utama. Sebaliknya hakim-hakim di negara kontinental, juga hakim-hakim kita di Indonesia, lebih banyak membatasi diri. Mereka berkewajiban untuk memberikan suatu putusan, tetapi mereka juga terikat pada undang-undang. Mereka masih hams berpegang teguh kepada undang-undang sebagai prinsip legalitas yang mempakan karakteristik bagi negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental atau civil law system yang menamakan diri sebagai recht staat atau negara hukum termasuk Indonesia. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita tetap menganggap hakim sebagai orang yang menegakkan hukum dan sumber yang membahami hukum itu sendiri. Dalam menerapkan hukum atas kejadian-kejadian konkrit, hakim hams memperhatikan keadaan-keadaan dan perimbangan-perimbangan sosial yang senantiasa bembah-ubah. Hakim tidak akan menemukan hukum dalam arti mengadakan suatu "penyelesaian" dengan melakukan silogisme seperti: kejadiankejadian objektif lalu aturan hukumnya kemudian konklusinya, putusan sebagai sanksi yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh suatu aturan hukum itu. Dapat pula dikatakan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang di satu pihak dan pelaksana undang-undang di lain pihak, terutama dan khususnya hakim kedua-duanya silih berganti berhubungan dengan yang disebut penetapanpenetapan hukum ini. Pembentukan undang-undang dapat menetapkan undangundang baik sebagai sesuatu perwujudan atas penemuan hal-hal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun bersifat merintis hal-hal yang menjadi acara pembangunan masyarakat itu sendiri.9 Tetapi kenyataan hidup yang senantiasa tumbuh dan perubahan atas dirinya menyebabkan situasi mengejar antara undang-undang yang telah ada dan batas maksimum kemampuannya dengan perintisan kembali serta pengarahan oleh undang-undang "barn" terhadap pembaharuan-pembaharuan sosial serta perubahan-perubahannya. Oleh karenanya hakim pun senantiasa dihadapkan kepada persoalan-persoalan seperti yang telah dikemukakan tadi, yaitu langsung sebagai pelaksana undang-undang atas kejadian sehari-hari yang dalam perkembangannya masih berada dalam batas luas lingkup daya berlakunya undang-undang itu sendiri atau telah sampai kepada bagian akhir dari daya berlakunya undang-undang itu sehingga harus "menciptakan" di samping menemukan hukum itu sendiri. Dalam hal inilah diperlukan bagi seorang hakim itu harus memiliki keahlian dan keterampilan teknis yudisial dalam menemukan dan menciptakan hukum, sehingga is dapat merupakan 9 8 Bagir Manan, mengatakan ada dua instrumen yang dapat dipakai hakim yaitu pertama, ajaran hakim bukan mulut undang-undang. Kedua, pranata judicial review, salah satu dari instrumen itu yang menarik adalah ajaran hakim bukan mulut undang-undang, hakim berhak menolak menerapkan atau mengenyampingkan undang-undang yang sewenang-wenang atau tidak adil, atau sekurang-kurangnya melakukan penemuan hukum (penafsiran, konstruksi, dan lain-lain) untuk menemukan putusan yang benar dan adil Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia pengisian kekosongankekosongan hukum, sementara belum dikejar oleh pembentuk undang-undang dengan penciptaan undang-undang barn pula. Untuk sekedar penyegaran perlu dengan singkat diuraikan mengenai hubungan antara hukum dan penemuan hukum, sebagai hal yang merupakan masalah barn dalam mengisi kekosongan pembentukan undang-undang. Pada umumnya orang tidak lagi berpendapat bahwa "dalam suatu negara hanya pembentuk undang-undang yang berhak menciptakan tertib hukum, dan yang akan berlaku bagi semua kemungkinan-kemungkinan kejadian. Dahulu orang memang berpendapat demikian, yaitu bahwa mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang tidak diberi wewenang lain lagi dan dalam bentuk apapun berhubung dengan penerapan undang-undang.10 Hanya pembentuk undang-undanglah berwenang untuk mengisi semua kemungkinan kekurangankekurangan itu. Begitu pula untuk mentafsirkan undang-undang, sehingga hakim hanya sebagai mulut atau corong undang-undang (bouche de la loi). 4. Penemuan Hukum dan Perubahan Sosial Di dalam kepustakaan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit atau proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das Sain) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang hams diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Diketahui bahwa pikiran seperti itu ditonjolkan oleh teori-teori Jean Bedin dan Montesquieu, 11 yaitu hubungan kekuasaan antara pembentuk undang-undang dan kekuasaan peradilan. Di sini dikaitkan dengan pendapat bahwa perundang-undangan suatu negara merupakan suatu kesatuan yang logis sistematis, dan berdasarkan pendapat ini dikemukakan bahwa putusan-putusan mengenai kejadian-kejadian yang konkrit selalu dapat ditarik dari undang-undang. Penerapan hukum dengan demikian hanya akan merupakan deduksi yang bersifat logis belaka terutama dalam abad yang lewat, pandangan demikian sangat berkuasa dalam hal "penemuan hukum.11 10 11 Sudikno Mertukusumo, mengemukakan bahwa penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin. Montesquieu, The Spirit of the Laws dalam Bagir Manan,bahwa keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim adalah berkaitan dengan fairness dan impartiality, untuk menjamin agar suatu sengketa atau pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara fair dan tidak memihak, diperlukan badan peradilan dan hakim yang netral. Itulah sebabnya kekuasaan peradilan hams terpisah dari legislatif dan eksekutif atau pengaruh dari kekuasaan lain. Untuk menjamin netralitas, tidak 9 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang, akan tetapi di dalam kenyataannya problematik penemuan hukum ini tidak hanya berperan pada kegiatan hakim dan pembentuk undang-undang saja. Penemuan hukum boleh dikatakan merupakan problematik setiap pencari keadilan yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan hukum untuk peristiwa konkrit. Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme atau bentuk pikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang dan premis minornya adalah peristiwa atau kasusnya, sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis, yaitu suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Tetapi, pandangan demikian itu mulai ditinggalkan di abad modern sekarang ini. Di Perancis. Fancois Geny mengemukakan kritik dalam bukunya, is mencela pandangan aliran seperti dikemukakan di atas tadi, yaitu yang berpangkal tolak dari suatu fiksi kesempurnaan undang-undang. Dia mengemukakan pula suatu teori barn mengenai sumber hukum yang terpadu di dalam "librerecherche scientifique" sebagai sumber asas-asas hukum, yang seyogyanya diterapkan oleh hakim apabila undang-undang dan kebiasaan yang didukung oleh "autorite dan tradition" mengandung kekurangan-kekurangan. Demikian pula di Jerman tumbuh dan kemudian diperkembangkan, antara lain oleh Von Jhering, yang disebut "interessenjurisprudenz", dan selanjutnya diikuti sosiologi hukum (Eugen Ehrlich). "freirechtsbewegung" dari Flapius. Di Amerika kita lihat realis-realis radikal seperti O.W. Holmes dan Jerome Frank, begitu pula penulis-penulis B. Cardozo dan Roscoe Pound, yang secara radikal memutuskan hubungan dengan fiksi-fiksi itu.12 Semua aliran ini menolak pikiran kesempurnaan undang-undang dan menganggap perlu adanya pembentukan hukum oleh alat-alat yang dibebankan tugas menerapkan undang-undang; dan merekalah yang akan mengisi 12 10 berpihak dan fair, kekuasaan kehakiman yang terpisah harus merdeka dan ada kebebasan hakim (makalah, 2012:7) Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (Pengantar Filsafat Hukum), 1996:15. Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia kekurangan-kekurangan dalam hukum. Semua aliran ini, kecuali aliran realitas radikal dari Amerika, banyak sedikit masih berpegang kepada artian sentral dari undang-undang yang berlaku, yang akan mengikat hakim sebagai tujuan karyanya. Juga "freirechtsbewegung" mengikuti pandangan seperti ini. Geny, masih berpegang teguh kepada metoda penafsiran menurut sejarah undangundang, yang didasarkan kepada kehendak pembentuk undang-undang, dan menggunakan metoda-metoda penafsiran lainnya semata-mata hanya untuk menetapkan tentang kehendak pembentuk undang-undang pada waktu terjadinya undang-undang yang bersangkutan. Ia berpendapat demikian karena didorong alasan-alasan "kepastian hukum". Aliran-aliran lain ternyata bergerak lebih jauh lagi. Mereka menitikberatkan kepada metoda-metoda penafsiran menurut teleologis.13 Di sini isi undang-undang diorientasikan kepada perimbangan kepentingankepentingan yang dilihat dalam kaitan suasana hubungan yang tertentu, dan yang memerlukan agar undang-undang diterapkan. Dalam hubungan ini orang lalu menaruh perhatian terhadap asas-asas tertentu yang dalam hubunganhubungan sosial hams menetapkan tentang berat-ringannya kepentingan hukum itu, dan hakimlah yang ditunjuk berperan utama mengenai dan dalam segala sesuatunya. Sehubungan dengan hal tersebut, lalu timbul pertanyaan mengenai hubungan satu dengan yang lain antara pembentuk undang-undang dan peradilan. Sekarang mengenai segi ini dikatakan sebagian orang bahwa "Di satu pihak pembentuk undang-undang tidak pernah mampu menyiapkan dan mendugakan terlebih dahulu mengenai kejadian-kejadian di hari yang akan datang, apalagi memperhitungkan hal-hal seperti demikian itu; sehingga betapapun undangundang harus dikerjakan lebih jauh oleh yang menerapkan undang-undang; artinya hams diperhalusnya dan juga dilengkapi". Sebaliknya, mereka yang menerapkan undang-undang pun hams terikat kepada asas-asas dan perimbanganperimbangan kepentingan yang oleh undang-undang telah diberi bentuk positif. Pikiran seperti inilah yang dewasa ini menguasai pandangan tentang penemuan hukum, dikaitkan kepada perubahan-perubahan sosial. Dengan lain perkataan bahwa ada suatu pertumbuhan hukum yang sifatnya dinamis, dalam batas-batas kerangka perundang-undangan yang secara relatif sifatnya adalah konstan.14 Pusat dari perhatian menurut pandangan ini adalah masalah hubungan konstan dan dinamik, atau kepastian dan sifat berubah-ubah dalam proses pembentukan hukum. Dalam kepustakaan Anglo Saxion orang memmuskan persoalan ini sehubungan dengan yang disebut asas stare decisis (abiding by precedent). Di satu pihak orang mengakui adanya ikatan juridis formal dari 13 14 Soedikno Mertokusumo, Penafsiran Hukum, 1985:25. Hal seperti ini terlihat dalam tulisan Julius Stone, dalam Legal System and Lawyer's Reasoning, 1964: 73. 11 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 hakim terhadap ratio decindendi atas dasar stelsel precedent, sedangkan di lain pihak orang berpegang pada pandangan bahwa ikatan ini dibatasi oleh kebutuhan hukum baru,15 dan antara hubungan kemasyarakatan yang mengharuskan lebih jauh ada penghalusan dan pengerjaan terhadap asas hukum (ratio decidendi). Jika hal ini kita hubungkan dan dilihat dari perintisan masa depan peradilan pidana dan perkembangannya, maka dapat dikatakan bahwa masa depan peradilan pidana tidaklah hanya suatu pemekaran dari saat ini belaka. Sebabnya oleh karena pertumbuhan hukum adalah sesuatu yang secara prinsipiil bersifat "discountinued". Pertumbuhan hukum tidak berarti bertambahnya hal yang sama, melainkan hal yang sama menjadi lain. Untuk dapat memberikan bentuk dan isi kepada pertumbuhan ini, maka seorang ahli hukum pidana hams dijiwai oleh suatu kehendak yang mantap dan ulet untuk melihat, dan kemudian lalu berkeyakinan bahwa hal-hal di dunia ini akan selalu menjadi lebih baik lagi. Dia akan menghadapi lapangan pekerjaannya tidak sebagai sesuatu yang telah disediakan, terbuka oleh alam ditempatnya, tetapi sebagai suatu perencanaan (design) yang telah digariskan kepadanya untuk diarahkan kepada suatu cita-cita kehidupan yang mulia. Ia dapat memulai dengan melihat perencanaan itu secara historis, tetapi selanjutnya is dapat menempatkan perencanaannya sendiri di samping yang telah ada itu atau bahkan bertentangan dengan itu. Baru setelah dijabarkan secara demikian akan ada saat-saat kreatif dalam kehidupan ahli hukum tersebut bergulat dengan masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan. Sekarang cita-cita kemanusiaan dan pandangan kemasyarakatan mempunyai arti yang lebih besar sehingga masyarakat akan datang memerlukan pembentukan dan penegakan hukum yang wajahnya lain dari yang kemarin. Tetapi hukum yang sekarang ini tetap merupakan pangkal tolaknya di samping dasar-dasar kekecewaannya pula. Sehingga politik hukum pembentukan undang-undang hams mengacu kepada kondisi dan kebutuhan masyarakat, yang hams menjadi dasar pembentukan hukum yang dicita-citakan (rechtsidee) oleh bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Kedepan di dalam kenyataan hidup kemasyarakatan, persoalan bukanlah hanya untuk mendapatkan dan membentuk pengertian-pengertian serta cita-cita belaka, tetapi yang penting lagi adalah untuk mewujudkannya. Dengan demikian maka kenyataan-kenyataan sekitar pengusutan, peradilan, penjara dan pelaksanaannya, senantiasa akan merupakan hasil usaha cita-cita tentang halhal tersebut. Diukur kepada cita-cita itu maka kenyataan-kenyataan ini selalu tidak sempurna, dan karenanya pula hal-hal yang terjadi itu akan selalu ada jejaknya untuk diteruskan dan mengadakan perubahan-perubahan. 15 12 Lengemeijer, dalam bukunya Pengantar Studi Filsafat Hukum, mencatat bahwa manusia seringkali bertahan untuk taat pada suatu aturan hukum positif, selama dia masih berlaku, sekalipun aturan itu sebenarnya tidak adil, 1970: 186. Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia Hal tersebut mempunyai akibat bahwa selumh kompleks norma, dan begitu pula pandangan-pandangan serta pendapat mengenai segala sesuatunya ini selalu dan terus-menerus harus didiskusikan dan usaha ini tidak dibatasi hanya sebagai suatu soal teknis para ahli hukum saja, tetapi juga menjadi soal ahli-ahli kejuruan lain mengenai ilmu pengetahuan tentang kelakuan manusia, sedangkan pada akhirnya juga sebagai soal semua warga. Karena itu,16 sejak zaman Socrates orang memahami secara sistematis, bahwa akal memainkan peranan utama dalam pembentukan hukum. 5. Hakim dalam Pembentukan Hukum Sekarang kita lihat lebih jauh segi lain dari proses pembentukan hukum itu sendiri dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial, dengan memusatkan pandangan kepada masalah hubungan konstan dan dinamik, sifat kepastian dan berubah-ubah dalam proses pembentukan hukum, seperti dikemukakan di atas. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa masalah ini sebagai masalah konstansirelatif dan dinamik-relatif dalam pembentukan hukum, serta hubungan keduanya itu satu sama lain. Soal tentang konstansi-relatif dan dinamik-relatif dalam pembentukan hukum, begitu pula hubungan keduanya satu sama lain, hanya dapat dijawab apabila kita bersedia memperhatikan dan mengindahkan sifat norma hukum yang berlaku pada umumnya. Semua norma hukum yang berlaku terjadi hanya oleh karena kepada asasasas hukum materiil diberi bentuk juridis oleh badan hukum legislatif yang kompeten. Dalil ini mengandung pengertian bahwa hanya hukum positiflah yang merupakan hukum berlaku dan bahwa suatu hukum kodrat di luar hukum positif, jika dilihat dari segi keberlakuannya semata-mata, jadi terlepas dari karya mengpositifkannya oleh manusia, sebenarnya tidak ada. Tetapi pemberian bentuk juridis seperti demikian saja tidak bersifat menentukan terhadap norma hukum, tanpa memperhatikan isi norma hukum itu. Ia hanya mempunyai arti juridis di dalam hubungannya dengan asas-asas hukum materiil, yang karena pemberian bentuk oleh manusia lalu mendapat bentuk konkrit dan historis, dan karenanya pula menjadi norma hukum yang berlaku. Karenanya konstansi juridis dan dinamik dalam pembentukan haruslah ditarik terus dan dikaitkan balik kepada asas-asas hukum materiil maupun kepada pemberian bentuk juridis daripadanya. Pemberian bentuk juridis dan asas-asas hukum materiil itu berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan oleh karena yang satu hanya mempunyai arti jika dihubungkan dengan yang lain, maka kedua isi dari konstansi juridis dan dinamik itu berkaitan dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Asas-asas hukum materiil menentukan isi hukum yang berlaku. Ia bersifat konstan-relatif. Harus pula dipisahkan antara asas-asas hukum yang "umum" 16 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, 2004: 271. 13 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 dan asas-asas hukum yang "typisch". Pertama, asas yang bersifat umum dan aspek hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman yang fundamental (modus quo) tentang kenyataan. Oleh karena sifat umum dan aspek hukum merupakan dasar tertib hukum, maka asas-asas hukum umum ini harus dipositifkan dalam tiap-tiap tertib hukum yang berlaku. Tidak mengakuinya akan mengakibatkan hasil pembentukan hukum itu sebagai "bukan hukum" atau "yang hanya kelihatannya sebagai hukum". Tidak satu pun tertib hukum misalnya ada tanpa lembaga pembentuk hukum. Apabila suatu masyarakat menghindarkannya, dan sematamata ingin mendasarkan din kepada perasaan hukum yang spontan dari anggotaanggota masyarakat. maka tidak akan terjadi ketertiban hukum. Asas-asas hukum umum dan konstitutif ini merupakan dasar tiap-tiap tertib hukum. Oleh karenanya maka is memperlihatkan "konstansi juridis" yang tinggi sekali. Dalam stelsel-stelsel hukum belum berkembang wataknya kaku, satu jenis, satu bentuk dan tertutup. Dalam stelsel-stelsel hukum yang sudah berkembang, asas-asas hukum umum dan konstitutif ini terbuka, di samping diperdalam dan diperhalus oleh asas-asas regulatif dari moral juridis. Asas-asas hukum regulatif ini mempunyai konstansi juridis yang lebih terbatas daripada yang konstitutif. Mereka berfungsi hanya dalam stelsel-stelsel hukum yang telah jauh berkembang. Di samping asas-asas hukum umum hams dibedakan dengan asas-asas hukum yang tidak berdasarkan pada sifat yang umum dari aspek hukum, tetapi dalam struktur dari kehidupan bermasyarakat dan is berfungsi dalam semuaaspek pengalaman kita badan mengikat fungsi-fungsi dalam aspek pengalaman menjadi kesatuan struktur masyarakat. Sejauh sifat-sifat dan hubungan kehidupan bermasyarakat ini berfungsi di dalam aspek hukum, maka akan ada asas-asas hukum yang tipis, baik konstitutif maupun regulatif sebagai dasar di dalamnya. Apabila dalam proses pertumbuhan yang bersifat kulturhistoris ini ditinggalkan ikatan-ikatan primitifnya, maka akan lenyap pulalah asas-asas hukum primitif yang tipis itu. Dia ini mempunyai suatu konstansi terbatas, yaitu dia hanya merupakan dasar di dalam stelsel-stelsel hukum yang belum berkembang dan merupakan dasar di dalam proses pembentukan hukum itu. Juga di dalam stelsel-stelsel hukum yang telah berkembang kita akan temukan asas-asas hukum konstitutif yang tipis itu di dalam hubungan kehidupan bermasyarakat yang telah berbeda-beda. Lain daripada asas-asas hukum tipis yang bersifat primitif, asas-asas hukum typisch yang telah berkembang dipimpin oleh prinsip-prinsip hukum yang bersifat regulatif.Juga asas-asas hukum yang tipis, balk konstitutif maupun regulatif ini, dan yang telah berkembang pula mempunyai konstansi yang relatif. Selama suatu masyarakat yang telah berkembang itu mempertahankannya, maka asas-asas hukum yang typisch akan merupakan dasar bagi proses pembentukan hukum. Konstansi relatif dari semua asas-asas hukum ini terwujud dalam keadaan, yaitu dalam memberi bentuk juridis. Alat-alat hukum harus selalu dan terus14 Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia menerus akan mendesakkannya ke dalam kesadaran hukumnya. Dia tidak akan melanggar atau mengesampingkan asas-asas konstitutif itu. Jika dikesampingkan juga, maka is akan bersalah membentuk yang disebut "non hukum" atau "hal yang kelihatannya saja sebagai hukum". Hal ini berlaku pula bagi asas-asas hukum typisch yang telah berkembang, yang adalah konstitutif bagi stelsel-stelsel hukum yang telah mengadakan pembedaan-pembedaan. Selagi pembentuk hukum masih berpegang kepada asas hukum konstitutif dan hanya hertentangan dengan prinsip-prinsip moral juridis, paling jauh akan ada yang disebut "hukum yang tidak adil". Tetapi padanya masih ada sifat kekuatan hukum.Konstansi relatif dari asas-asas hukum yang typisch dan umum berhubungan dan tak dapat dipisahkan dari dinamik juridisnya asas-asas ini. Konstansi juridis dari asas-asas hukum materiil tidak boleh kaku dan statis. Asasasas itu tidaklah dinyatakan secara tetap dan sempurna, melainkan menunjukkan arti juridisnya itu dalam pertumbuhan hukum yang semakin kaya dan semakin dalam. Jadi konstansi relatif dari asas-asas hukum materiel sisinya yang lain adalah dinamik juridis, yang di dalam stelsel-stelsel hukum telah berkembang karena tuntutan prinsip-prinsip hukum regulatif lalu mencapai tingkat yang tinggi dan utama. Konstansi dan dinamik relatif dari asas-asas hukum materiil ini menyimpulkan bahwa proses pembentukan hukum yang dinamis ada dalam alatalat hukum yang kompeten. Baru di dalam proses pembentukan hukum inilah asas-asas hukum konstansi yang relatif dapat mengembangkan artinya yang dinamik. Sebaliknya dianggap pula bahwa proses pembentukan hukum yang dinamik mengandung di dalamnya asas-asas hukum materiil, yang tanpa dia tidak akan dapat terjadi hukum yang berlaku. Berikut ini sedikit tentang dinamik horizontal dalam proses pembentukan hukum. Di dalamnya termasuk perubahan dan pembentukan hukum pada tingkat yang sama dalam suatu daerah hukum materiil. Pembentuk undangundang biasa hams menyesuaikan perundang-undangan dalam arti materiil selalu kepada hubungan-hubungan hukum bare dan kebutuhan-kebutuhan barn. Demikian pula hakim. Dia ini pun hams memperhalus dan membangun peradilan yang telah letup itu dari sorotan keadaan-keadaan dan kebutuhankebutuhan yang barn. Tetapi dinamika yang bersifat horizontal di dalam dirinya itu sendiri mengandung adanya dinamika vertikal dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dimaksudkan proses pengwujudan lebih jauh dan pengindividualisasian dari banyak atau sedikitnya norma hukum yang bersifat umum melalui bermacam-macam anak tangga yang rendah dalam pembentukan hukum. Dinamikanya adalah sangat tergantung pada hirarki dari pembentukpembentuk hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah di dalam suatu muatan hukum materiil. Suatu perundang-undangan dalam arti formal yang banyak sedikitnya bersifat umum haruslah oleh hakim lebih jauh diwujudkannya dalam hal adanya perkara dengan memperhatikan kejadian yang diadili itu. Di sini pembentukan hukum dari suatu anak tangga yang lebih tinggi bergerak menuju kepada suatu anak tangga yang lebih rendah dalam geraknya yang vertikal. 15 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Perundang-undangan dalam arti yang formal hams selalu dalam garisnya yang horizontal diserasikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru, tetapi isi tetap merupakan “huruf-huruf mati”, apabila dia tidak diterapkan oleh pembentuk hukum yang lebih rendah dalam garis vertikalnya itu atas kejadiankejadian konkrit. Pembentuk hukum yang lebih rendah seharusnya lebih lanjut menyesuaikan peradilan konstannya itu terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum baru. Dan peradilan yang berjalan terus ini dapat menimbulkan pula lagi suatu perundang-undangan dalam arti formal yang lebih baru, dan begitulah seterusnya. Tetapi keseluruhan proses pembentukan hukum yang dinamis, baik dalam arti horizontal maupun yang vertikal tidak mungkin tanpa konstansi dan dinamik relatif dari asas-asas hukum materil. Adalah asas-asas hukum materiil yang bersifat konstitutif dan regulatif yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sedangkan sebaliknya asas-asas ini akan mengembangkan arti isi juridis daripadanya itu di dalam pembentukan hukum yang dinamis. Selalulah di dalam hal itu hams ada suatu harmoni antara konstansi relatif dan dinamik relatif dari pembentukan-pembentukan hukum. Konstansi relatif itu tidak boleh dijadikan mutlak, oleh karena ini akan menimbulkan pembekuan dalam kehidupan hukum. Dan jangan pula sampai dinamik relatif itu ditekankan dengan mengorbankan konstansi relatif, oleh karena dengan demikian akan timbul ketidakpastian hukum dan kesewenangwenangan. Adalah menjadi tugas bagi aparat penegak hukum yang kompeten untuk mewujudkan harmoni ini. Mereka adalah pendukung proses pembentukan hukum dinamis di dalam daerah hukum materiil mereka. Di atas bahu merekalah diletakkan tanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan hukum melalui pengwujudan secara positif dan dinamik dari asas-asas relatif konstan dan dinamik itu terhadap cita-cita hukum dan pembangunan masyarakat.Sekarang mengenai perubahan masyarakat in. sendiri. Walaupun telah banyak dibicarakan dan dikaitkan orang hukum dengan perubahan masyarakat, namun tidak banyak ahli hukum mempunyai minat untuk melihat lebih jauh dan dengan baik hal-hal menyangkut perubahan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya mengenai perubahan masyarakat telah banyak diteliti dan dibicarakan orang. Menurut hemat kami tidaklah sempurna seorang ahli hukum meninjau perubahan hukum yang dikaitkan domean perubahan masyarakat tanpa mengerti lebih jauh mengenai hal-hal menyangkut perubahan masyarakat ini sendiri, yang telah ditemukan oleh ahli ilmu pengetahuan lain. Perubahan akan terjadi di setiap masyarakat dan di setiap waktu. Akhirakhir ini hal perubahan masyarakat banyak mendapat perhatian, terutama setelah dikonstatir, bahwa apabila suatu masyarakat belum maju mengadakan hubungan lebih banyak dengan masyarakat lain yang telah maju, maka terjadi perubahanperubahan yang cepat dan kadang-kadang juga menimbulkan kekacauankekacauan. Demikianlah misalnya teknik-teknik baru menggeser 16 Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia pola-pola bekerja dan kerja sama; adanya lalu-lintas keuangan mengakibatkan perubahanperubahan yang banyak dan berturut-turut di dalam tukar-menukar, menimbulkan masalah-masalah keuangan internasional, dan menimbulkan persoalan-persoalan bagaimana kemakmuran dapat dicapai lebih banyak lagi. Timbul bermacammacam pekerjaan baru, dan semuanya ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan. Dalam hubungan ini pula kadang-kadang timbul pelbagai disintegrasi. Yang disebut "control social'; juga lalu kehilangan kekuatannya, sehingga dalam beberapa hal menimbulkan bentuk kejahatan baru dan meningkatnya kejahatan. Tetapi tidak hanya yang jelek terjadi, melainkan terjadi juga hal-hal yang baik, di mana masyarakat dapat dan berhasil menyesuaikan diri, lalu ditingkatkan kehidupan materiil anggota masyarakat. Ditingkatkan dan bertambah-tambahnya tingkat serta kompleksnya keadaan ekonomi dan politik mereka, tanpa secara radikal melemparkan segi-segi moralnya. Tetapi di dalam tiap-tiap kejadian itu ternyata bahwa situasi kemasyarakatan yang baru tidaklah begitu saja merupakan suatu campuran cara-cara lama dan cara-cara baru, melainkan merupakan suatu fenomena sosial yang serba baru pula yang menghendaki suatu studi khusus lagi. Inilah yang kami kemukakan tadi bahwa penyesuaian pembentukan hukum terhadap perubahan-perubahan masyarakat menghendaki pengertian ahli hukum terhadap hasil-hasil studi mengenai perubahan-perubahan masyarakat tersebut. Kehidupan sosial itu sangat memuaskan akan cenderung untuk menahan diri dalam melakukan perubahan-perubahan. Mungkin sekali bahwa aturanaturan yang barn itu mengandung hal-hal yang lebih baik tetapi diperlukan sekali beberapa waktu lama terjadinya kebimbangan-kebimbangan sebelum peraturan yang baru itu betul-betul dapat menjadi sama diketahui dan digunakan oleh semua orang. Masa-masa terjadinya perubahan masyarakat yang besar biasanya ditandai oleh suatu kemunduran di dalam wibawa dari aturan-aturan dan semakin besarnya bergantung orang kepada eksperimeneksperimen, dan rasionalitas di dalam tindakan-tindakan. Inilah beberapa pokok berkaitan dengan perubahan masyarakat yang kiranya perlu mendapat perhatian para ahli hukum di dalam mengkaitkannya dengan pembentukan hukum, baik apakah itu akan mendahului peristiwaperistiwa seharihari ataupun penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa itu sendiri. Dengan lain perkataan, seorang ahli hukum yang baik untuk dapat selalu menyesuaikan hukum yang diterapkannya itu, dan yang disusunnya itu, dengan kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari, termasuk perubahan-perubahan masyarakat hams selaras, di samping ilmu pengetahuan hukumnya mendalami pula hal-hal yang bersangkutan dengan kemasyarakatan. Ini adalah suatu 17 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 tuntutan mutlak dewasa ini, walaupun masih banyak sekali ahli hukum yang tidak menyadarinya.17 Memang tepatlah kiranya, sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan dinamis penemuan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undangundang. Oleh karena itu diakui bahwa dalam hal kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan penafsiran undang-undang. Meskipun orang makin lama meninggalkan pandangan legistis atau positivisme undang-undang, tetapi pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem. Semua hukum terdapat dalam undang-undang dan hanya kalau ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka hakim boleh menafsirkan. Dalam cara pemecahan semacam ini sistem menjadi titik tolak. Di sini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. C. KESIMPULAN DAN SARAN Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi berhubung ada peraturan-peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan hams dipulihkan. Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya khususnya hukum materiil maupun formil. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan, namun kini belum optimal berfungsi untuk menyelesaikan administrasi peradilan seperti masih bertumpuknya putusan-putusan yang belum sampai kepada para pencari keadilan. Hak pencari keadilan untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (asas fair trial), diperlakukan sama dengan sesama pencari keadilan (asas equality before the law), serta memperoleh putusan dalam waktu yang wajar, sederhana dan biaya ringan (asas contante justitie) adalah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pencari keadilan. Bagi pencari keadilan yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang diperlukan itu tidak jarang hams mengeluarkan biaya ekstra yang tidak sedikit dan kalau itu yang terjadi dalam kenyataan maka sudah dapat dipastikan asas peradilan dengan biaya ringan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya 17 18 Lihat, L.H.C. Hulsman, Frustratie en Justitie, dalam P.J. Verdam, Overheid en Frustratie, Deventer, 1967, page 66-67). Khususnya Sosiologi, tidak dapat disangkal harus ada sebagai alat di tangan ahli hukum dan tidak boleh diabaikannya. Bukankah "hukum" itu adalah suatu gejala sosial yang relevan. Kebebasan Hakim dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia serta berakibat biaya pengeluaran tersebut dapat dipastikan secara illegal dan dengan demikian berakibat pada sistem peradilan yang buruk, oleh karena itu perlu ditingkatkan kesadaran dan integritas aparat peradilan disemua empat lingkup peradilan yang ada di Indonesia. Betapa pentingnya penemuan hukum dikaitkan kepada perubahanperubahan sosial yang dilaksanakan oleh seorang pembentuk hukum termasuk hakim dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik bagi putusan hakim yang berkeadilan dan bagi masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan ke arah terjadinya perubahan atau pergeseran dari "hakim terikat" ke arah "hakim bebas", dari "keadilan menurut undang-undang" (Normgerechtigkeit) ke arah "keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusannya (Einzelfallgerechtigkeit), dari berfikir dengan mengacu kepada sistem (Systeemdenken) ke arah berfikir dengan mengacu kepada masalahnya (Probleemdenken). DAFTAR PUSTAKA Bagir Manan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri, (makalah) disampaikan dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Balitbang Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Oktober 2012. Budiono Kusumohamidjojo, 2004, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Parahiangan, Bandung. Harifin A. Tumpa, 2012, Kemandirian Hakim, (makalah), disampaikan dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Balitbang Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Oktober 2012. Julius Stone, 1964, Legal System and Lawyer's Reasoning, L.H.C. Hulsman, 1967, Frustratie en Justitie, dalam P.J. Verdam, Overheid en Frustratie, Deventer. Lengemeij er, 1970, Pengantar Studi Filsafat Hukum, Roscoe Pound, 1996, An Introduction to the Philosophy of Law (Pengantar Filsafat Hukum). Sudikno Mertokusumo, 2001, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Liberty Yogyakarta. Sidney Smith, 1976, Nations fall when judges are injust, because there is nothing which the multitude think worth defending. Van Eemeren, et al, 1987, Argumenteren voor juristen, Wolters-Noordhoff, Groningen. Van Eikema Hommes, Logika en rechtsvinding, Vrije Universiteit, Amsterdam tanpa tahun. Van Gerven dan Leijten, 1981, Theorie en Praktijk van de rechtsvinding, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 19 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Vranken, J.B.M., 1978, Kritiek en Methode in de Rechtsvinding, Kluwer, Deventer. Wiarda, G.J., 1988, Typen van Rechtsvinding, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 20 GOOD GOVERNANCE DAN PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA: REFLEKSI DALAM PENELITIAN SOSIO-LEGAL1 Herlambang P. Wiratraman Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, PhD Researcher, Faculteit der Rechtsgeleedheid, Universiteit Leiden [email protected] Abstrak Dalam dekade terakhir pasca Soeharto, Good Governance (GG) telah sering mendengar seperti 'mantra' GG tampaknya mudah diucapkan banyak bicara, formal, dan tumbuh menjadi cita-cita politik yang dominan serta konstitusional dan publik wacana administrasi besar yang telah berakar dalam hukum, kebijakan, dan pendidikan tinggi. Seperti ayam yang berkokok di pagi hari, is terns berbicara di pagi hari, lebar kotak bibit 'governance', seperti 'tata kelola kehutanan yang baik', 'tata kelola keuangan yang baik', 'good university governance', dan banyak lainnya. GG, dalam konteks itu, tampaknya seperti nutrisi yang tepat untuk mengatasi kelemahan sistem hukum Indonesia, birokrasi yang korup, dan kepemimpinan politik predatoric. Dalam hal ini, harus dilihat lebih dekat, apa yang sebenarnya keunggulan yang dimiliki saat GG adalah berbicara? Jelas, hukum adalah salah satu alat untuk memastikan pengoperasian mantra dalam pelaksanaannya, dan didasarkan pada penelitian utama yang dilakukan pada tahun 2005-2006, dengan fokus pada isu Reformasi Hukum dengan menerapkan pendekatan sosio-legal. Akibatnya, penelitian ini memberikan fakta yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan cita-cita bangunan politik atau diformalkan atau terwujud hukum dan kebijakan. Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa GG dalam konteks reformasi hukum di Indonesia sebenarnya sangat menakutkan dan melemahnya jaminan hak asasi manusia. Hukum, khususnya produk legislasi dan lembaga, serta transmisi mesin yang dominan dalam mengadvokasi pasar bebas (pasar reformasi hukum ramah gratis). Mungkin, kesimpulan tidak populer di tengah-tengah pidato ejaan bising GG dan proyekproyeknya. Namun demikian, Indonesia saat ini menunjukkan kelanjutan dari korupsi besar-besaran, pelanggaran HAM, impunitas dan semua situasi non-perlindungan dalam sistem hukum Indonesia. Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Reformasi Hukum, Pendekatan Sosio Legal Abstract In the last decade post Soeharto, Good Governance (GG) has been often heard like a `mantra'. GG seems easily uttered talkative, formalized, and grew into a dominant political ideals as well as major constitutional and public administration discourse which have rooted in law, policy, and higher education. Like a rooster 1 Diambil dari presentasi Pelatihan Socio-Legal, Epistema, Jakarta, 15-16 April 2013. Diolah kembali untuk keperluan Jurnal di Mahkamah Agung Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 crowing in the morning, he continued to speak out in the mornings, wide box spawn 'governance, such as 'good forestry governance, 'good financial governance, 'good university governance, and many others. GG, in that context, seems like an appropriate nutrition to overcome the weakness of the Indonesian legal system, corrupt bureaucracy, and the predatoric political leadership. In this regard, it should be viewed more closely, what is actually superiority owned when GG is talked? Obviously, the law is one of the tools to ensure the operation of the mantra in its implementation, and based on master research conducted in 2005-2006, focusing on the issue of the Law Reform by applying a socio-legal approach. As a result, this study gave the fact which is different or even contrary to the ideals of political buildings or formalized or materialized law and policy. For example, one study showed that the GG in the context of legal reform in Indonesia actually very sinister and weakening the guarantee of human rights. Law, especially product of legislation and institutions, as well as its machinery transmission are dominant in advocating free market (free market friendly legal reform). Perhaps, the conclusions is not popular in the middle of the noisy speech spelling of GG and its projects. However, Indonesia today shows the continuation of massive corruption, violation of human rights, impunity and all the non protection situation in the Indonesian legal system. Keywords : Good Governance, Law reform, Sosio Legal approach 1. Mengapa Good Governance? Sungguh mengenaskan perkembangan ketatanegaraan Indonesia hari ini. Sejak reformasi bergulir, jumlah kelembagaan negara yang dibentuk barn mencapai lebih dari 70 lembaga, baik di bawah pilar kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudisial. Demokrasi sendiri berjalan menempuh rute prosedural yang sarat dengan politik representasi liberal pemilu, tanpa bisa lagi mengidentifikasi keperluan mendasar bagi pemenuhan kesejahteraan sosial. Desentralisasi melahirkan penyebaran korupsi yang kian sistematik, rapi dan menjadi keseharian politik dan hukum. Elit-elit lokal predatorik yang merampok sumberdaya alam dengan ditopang kebijakan dikriminatif, represif, dan kekuatan aliansi politik-ekonomi yang dominan. Dalam rangka merawat kepentingan aliansi tersebut, desentralisasi pula menyuburkan 'privatized gangsters' untuk menjaga keberlanjutan kepentingan. Hak asasi manusia, sekalipun di awal telah melengkapi suasana konstitusionalisme UUD RI 1945, dalam prakteknya hak-hak asasi manusia pun diseleksi untuk menuruti kebutuhan liberalisasi pasar dan pelanggaran terus saja terjadi. Kekerasan, pemiskinan, pelemahan penegakan hukum, dan impunitas masih saja dominan di Republik ini. Salah satu wacana yang paling atraktif, ofensif, dan pada akhirnya terformalisasi dalam wacana dan hukum ketatanegaraan adalah good governance Ia hadir seperti mitos, yang begitu gampang dipercaya baik oleh pengambil dan pelaksana kebijakan, kaum intelektual dan celakanya, sebagian besar rakyat. Rasa penasaran inilah yang menggerakkan, apa yang sebenarnya 'good' dalam 'good governance', dan mengapa? Apa hukum berikut institusi (hukum) yang 22 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia dipergunakan untuk mentransmisikan wacana itu? Apakah is juga memperbincangkan atau mengupayakan perlindungan dan pemenuhan HAM, ataukah tidak? Bilamana good governance kuat ditancapkan, mengapa situasi yang disebut di muka masih saja kerap terjadi? Penasaran kian bertambah tatkala kawan Rival Gulam Ahmad (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK), menghadiahi sebuah buku yang ditulis Rita Abrahamsen,2 yang diberikannya saat jumpa di suatu pendidikan hukum kritis untuk petani miskin di Kendal, Jawa Tengah, tahun 2005. Buku yang berangkat dari studi di empat negara Afrika itu menginspirasi untuk mengkontekstualisasi dalam konteks Indonesia, dan mempertegas keterkaitannya dengan hukum.3 2. Socio-Legal: Awal Ketertarikan Menyadari sedari awal, kajian hukum perundang-undangan tidaklah cukup menjawab pertanyaan tersebut. Ditambah pula, interaksi personal dalam mengembangkan program di HuMa saat itu (Program II: Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis), mendapati situasi yang memang tidak mungkin untuk tidak mendayagunakan disiplin ilmu lain untuk memahami hukum dan penegakannya. Sekalipun demikian, penelusuran dalam rangka penelitian good governance setidaknya dilandasi atas tiga hal : Pertama, pertanyaan itu sendiri kunci yang mengarahkan pada metodologi yang lebih presisi. Kedua, menempatkan kajian socio-legal menjadikan lebih memungkinkan menjangkau segala disiplin ilmu, memberdayakan segala teori sosial (politik dan ekonomi) untuk membedahnya, sekaligus mendapatkan argumentasi yang lebih melegakan. Ketiga, dibuat dalam kerangka master thesis program HAM dan Pembangunan Sosial, sehingga jelas tak memungkinkan studi hukum doktrinal semata.4 Salah satu obyek yang hendak dikaji adalah isu legal reform dalam kerangka good governance di Indonesia. Karena isu legal reform demikian luas, maka untuk memastikan proses dan hasilnya lebih dalam, dipilih sejumlah legal reform yang berkaitan dengan isu hak buruh (ketenagakerjaan). Apalagi, waktu yang tersedia dalam proses penelitian dan menulis adalah 4 bulan kerja. Tentunya, pula disadari ada keterbatasan dalam prosesnya, atau bahkan hasil yang dikemukakan. 2 3 4 Abrahamsen, Rita (2000) Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa. New York : Zed Books. Keterkaitan dengan hukum ini yang kurang mendapat perhatian dalam studi Abrahamsen (2000). Untuk alasan ketiga ini, saya harus berterima kasih kepada Prof Soetandyo Wignyosoebroto, yang merekomendasikan ambil program master di Mahidol University, yang dibilangnya saat itu sebagai "menyeberangi ilmu, melintasi pengalaman berbeda...". Sekalipun tak memungkinkan sekadar penelitian hukum normatif atau doktrinal, dalam proses perumusan penelitian hingga ujian senantiasa melibatkan penguji dari Fakultas Hukum. 23 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 3. Tinjauan Hukum Perundang-undangan Dalam proses penelitian, kajian hukum perundang-undangan beserta kebijakan merupakan titik awal berangkat penyelidikan. Kompilasi atas norma terkait good governance, HAM dan isu ketenagakerjaan dikumpulkan. Bahan hukum ini penting untuk kemudia dipetakan sejarah, konteks dan perdebatan yang melatarbelakangi kelahirannya. Analisis hukum dilakukan terhadap bahan-bahan tersebut, dengan pertanyaan utama: Apa landasan hukum tentang good governance? Bagaimana hukum menjelaskan good governance ke dalam aturan implementasi / operasionalnya? Isu apa saja yang terkait dengan good governance? Sungguh, berbasis bahan dan analisis tersebut, terlihatlah bentangan norma, asumsi, isu, institusi, kewenangan, aturan lebih rendah, serta mekanisme yang keseluruhannya berkait dengan isu good governance. Ini merupakan modal awal dalam melucuti 'good governance' dalam kebijakan dan konstruksi perundangundangan. 4. Membongkar Mitos Dengan mudah kita menyaksikan atau mendengar dari dekat bahasa santun nan elok 'good governance', tetapi dengan sangat gampang pula di sekitar kita terlihat centang perenang terjadi korupsi sistematik, legalisasi suap antar lembaga kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. Sepertinya, beda tipis antara apa yang disebut dengan 'good' (baik) dengan 'had' (buruk) atau poor' (miskin) dalam tata kelola pemerintahan, karena keduanya berjalan seiring bak lintasan rel kereta yang didisain kuat menancap dengan tantalan' teori dan mistifikasi kekuasaan, yang keluar masuk stasiun mengangkut (baca: memperdagangkan) penumpang sebanyak-banyaknya. Persis seperti 'good governance' yang diinjeksikan dari negara satu ke negara lain yang menebarkan pengaruh tentang kebenaran absolut pengelolaan urusan negara (ketatanegaraan). Uniknya, tak lama berselang, mitos ini kian beranak-pinak dalam sejumlah mitos lainnya yang membuat teori-teori yang menopang di bawahnya sangatlah absurd, latah dan menggelikan karena telah jauh meninggalkan substansi serta paradigma ketatanegaraan. Lihat saja, 'good sustainable development governance' (Partnership Initiatives 2002), ' good financial governance' (Soekarwo 2005), „good environmental governance' (Wijoyo 2005: 44), 'good coastal governance', dan lain sebagainya. Kritik terhadap good governance bukanlah hal yang barn, karena banyak studi atau riset yang telah dilakukan untuk membongkar wacana ini dalam berbagai pendekatan, baik itu pendekatan politik, ekonomi, sejarah, hukum, sosiologi internasional, hubungan internasional dan pendekatan disiplin ilmu lainnya (Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; Parasuraman, et. al. 2004; Pieterse 2004; Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Selznick 1969; Gathii 1998; Hosen 2003). Bank Dunia merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkannya sebagai „program pengelolaan sektor publik‟ (public sector management program), dalam 24 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan (World Bank 1983: 46). Good governance dalam konteks ini merupakan suara pembangunan. Sebagai suara pembangunan, sesungguhnya is lebih menampakkan pendisiplinan demokrasi atau model ketatapemerintahan tertentu. Krisis di Afrika telah membawa pesan demikian jelas dalam mencetuskan suatu konsep barn mengenai 'governance' untuk menentang apa yang disebut Bank Dunia sebagai suatu 'crisis of governance' atau 'bad governance' (World Bank 1992). Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan p erang dingin telah menggambarkan latar dari suatu iklim umum dalam menyokong pasar bebas dan demokrasi liberal, dan hal ini telah secara dahsyat menunjukkan betapa good governance sebagai pemaksaan politik hukum oleh negara industrialisasi maju dan agen internasional (termasuk lembaga maupun negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan pasar (Abrahamsen 2000; Stokke 1995; Gathii 1998). Dalam konteks Asia, proyek-proyek good governance sesungguhnya telah lama diperkenalkan ke sejumlah negara, utamanya ke negara-negara yang memiliki ketergantungan atas bantuan hutang luar negeri. Proyek tersebut sama sekali tidak mempedulikan rezim yang berkuasa adalah rezim yang koruptif dan diktatorial. Di Indonesia, pada awal tahun 1990an sudah mulai diperkenalkan model ketatapemerintahan yang ramah terhadap kepentingan pasar, melalui skenario program penyesuaian struktural. Meskipun demikian, saat Soeharto masih berkuasa, proyek-proyek yang dikembangkan di Indonesia praktis gagal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Bahkan korupsi yang dilakukan atas bantuan hutang luar negeri tersebut diketahui Bank Dunia, namun Bank Dunia melakukan pembiaran atas hutang-hutang yang dikorupsi tersebut. Inilah yang disebut 'criminal debt' (hutang kriminal), yang ironisnya hams dibayar oleh rakyat dan dibebankan pada generasi bangsa pasca Soeharto (Winters 1999; 2002). Jadi apa yang disebut sebagai 'bantuan' oleh Bank Dunia, sebenarnya merupakan proses sistematik penghancuran yang tidak hanya ditujukan pada rakyat saat rezim Soeharto berkuasa, melainkan pula ongkos `pelanggengan kekuasaan diktator' yang memiliki konsekuensi panjang terhadap jutaan rakyat Indonesia di masa-masa berikutnya. Dalam situasi demikian, terlihatlah dengan jelas bahwa 'good governance' bersahabat dengan mekanisme-mekanisme siluman yang tidak berkepentingan atas demokratisasi dan hak asasi manusia. Tekanan Bank Dunia dalam urusan pembaruan ketatapemerintahan kian menguat disuntikkan setelah terjadinya krisis finansial di Asia di paruh akhir 1990an. Praktek dan justifikasi Bank Dunia melalui diagnosa antara ketatapemerintahan yang `buruk dan baik' menjadi wacana utama dalam mempengaruhi faktor-faktor kegagalan dalam konteks krisis tersebut, dan ini persis seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya di Afrika pada 1980an. Seining bersama dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa tahun 1998, seolah proponen neo-liberal diberi `pintu masuk' untuk kembali menanamkan proyek-proyeknya (juga melalui utang) kepada pemerintah. Ratusan juta dolar dikucurkan untuk pemerintah dalam membiayai pembaruan kebijakan dan institusi politik, hukum dan ekonomi, sehingga tak terelakkan bahwa good 25 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 governance menjadi arus utama pembaruan birokrasi dan hukum sebagai penopang proyek ketatapemerintahan tersebut. Desentralisasi yang terjadi di awal reformasi telah memuluskan dan menyuburkan wacana good governance, karena is menjadi sesuatu yang seksi, segar, populer, dan diucapkan secara berulangkali baik oleh pejabat tinggi hingga level yang paling rendah di daerah. Tak terkecuali, agenda-agenda gerakan menjadi ikut pula termoderasi dan mempercayai good governance sebagai obat mujarab bagi tatanan birokrasi politik-ekonomi Indonesia. Akademisi dan organisasi nonpemerintah pun latah mengucapkan wacana tersebut sebagai ikon barn yang menemani demokratisasi. Sejak reformasi bergulir, telah lahir banyak pusat studi maupun proyek-proyek good governance yang dipesan melalui perguruan tinggi, dari mulai isu yang lekat dengan pembaruan hukum, pembaruan peradilan, desentralisasi, penganggaran, hingga soal legal drafting. Begitu juga organisasi non-pemerintah yang secara kuat pula mentransmisikan gagasan good governance melalui isu yang tidak jauh berbeda. Mengapa transmisi wacana good governance tersebut demikian kuat diusung oleh Bank Dunia dan kemudian ditransplantasikan dengan rapi oleh agen-agen negara maupun non-negara? Kita bisa mulai membedahnya dari sisi konseptual, dan lalu dilanjutkan dengan memetakan bagaimana kerangka konseptual tersebut menjadi sangat dominan dipaksakan ke negara-negara selatan, termasuk di Indonesia. Dalam laporannya tahun 1989, Bank Dunia telah mengekspresikan gagasan "Upaya untuk menciptakan suatu kemampuan lingkungan dan untuk membangun kapasitas-kapasitas akan dibuang bila konteks politik tidak mendukung. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik memerlukan pembaharuan politik. Ini berarti suatu tindakan bersama melawan korupsi dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menata suatu contoh baik, dengan memperkuat pertanggungjawaban, dengan mendukung debat publik, dengan memelihara suatu pers bebas. Ini juga berartimembantu perkembangan akar rumput dan organisasi non-pemerintah seperti serikat petani, perkumpulanperkumpulan, dan kelompok-kelompok perempuan" (World Bank 1989). Dengan langgam bahasa yang hampir sama, Bank Dunia telah menyatakan pula, "Good governance dilambangkan dengan dapat diperkirakan (predictable), terbuka (open) dan pembuatan kebijakan yang tercerahkan (enlightened policymaking), suatu birokrasi diilhami dengan bertindak etos professional dalam pemajuan fasilitas publik, rule of law, proses-proses transparan, dan masyarakat sipil yang kuat berpartisipaso dalam kepentingan publik. Ketatapemerintahan yang miskin (poor governance) di sisi lain dikarakteristikan dengan pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang, birokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sistem perundangan yang tidak adil dan tidak bisa ditegakkan, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, suatu masyarakat sipil yang tidak bisa menikmatik kehidupan publiknya dan korupsi yang meluas." (World Bank 1994: vii). 26 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia Dalam mengkampayekan good governance, Bank Dunia telah memprogramkan suatu program pembelajaran dan telah memperkenalkan konsep ketatapemerintahan, Good governance merupakan suatu manual yang didefinisikan sebagai implementasi efektif kebijakan dan provisi pelayanan yang yang responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan warganya. Good governance melekat pada kualitas, seperti akuntabilitas, responsif, transparan, dan efisiensi. Ia mengasumsikan kemampuan pemerintah untuk mengelola sosial, perdamaian, jaminan hukum dan tatanan, mempromosikan dan menciptakan kondisi-kondisi yang perlu untuk pertumbuhan ekonomi dan mamastikan suatu level minimum jaminan sosial (World Bank 2002). Definisi yang demikian sesuangguhnya telah tetap dan secara kuat dipertahankan untuk menyokong aturan main bahwa membuat pasar bekerja secara efisien dan lebih problematiknya, Bank Dunia mengoreksi kegagalan pasar (Bank Dunia 1992). Sejumlah dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia, khususnya dalam menegaskan isu-isu penting akuntabilitas, sesungguhnya ditujukan dalam rangka mengupayakan pembaharuan untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang diperlukan dalam proses liberalisasi pasar. Konsep politik ekonomi yang demikian sesungguhnya berfokus pada model demokrasi liberal dan liberalisasi ekonomi, dan good governance-nya pun merupakan model neo-liberal, yakni 'good governance free market assistance' (Wiratraman 2006). Watak neo-liberalisme good governance dapat dilihat dari sasaran-sasarannya yang senantiasa berpusat pada efisiensi pengelolaan sumberdaya dan menopang pasar bebas. Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi. Sungguh, elemen-elemen ini juga menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah eforia reformasi, namun elemen kunci tersebut sebenarnya menyimpan rencana besar untuk melucuti peran-peran negara di sektor publik dan menggantikannya dengan peran dominan swasta atau privat. Urusan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah urusan yang penting dalam skema good governance ini, meskipun mandat tanggung jawab hak asasi manusia bertumpu pada peran utama negara (vide: Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen). A contrario, berarti, good governance yang demikian hanya akan menempatkan posisi pasar secara dominan, dan urusan-urusan publik yang dimaksudkan pun telah diseleksi (baca: dipangkas) berbasis pada iklim liberalisasi pasar. 5. Good Governance dan HAM: Inkoheren plus Subordinasi Dalam riset disimpulkan bahwa Good Governance tak ubahnya semacam teknologi peluruhan kedaultan rakyat. Selain bentuknya yang imperatif dan penuh dengan mitos `kebaikan', good governance juga menggunakan teknologi yang dalam prakteknya justru mengsubordinasi atau bahkan bertentangan dengan upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia seperti mantra dalam sirkuit pembangunan yang membentuk ketatapemerintahan politik dalam abad globalisasi. 27 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Bagaimana teknologi ini bekerja dan berpengaruh dalam mensubordinasi hakhak asasi manusia? Pertama, munculnya good governance tidak terpisahkan dengan tekanan untuk liberalisasi pasar dalam bentuknya yang lebih santun. Oleh sebabnya, good governance sekarang lebih tampil dalam diskursus hak asasi manusia, namun terseleksi dan mengharuskan ramah terhadap pasar (market friendly human rights paradigm). Meskipun banyak yang berpendapat bahwa good governance sangat terkait dengan upaya maju hak asasi manusia, namun dalam sejumlah penelitian dan kajian membuktikan sebaliknya. Mulai dan konstruksi wacana, paradigma, dan rancangan good governance yang ditampilkan dengan dominan neo-liberalisme yang memaksakan negara-negara selatan mengikutinya, sungguh dinamika antara teks dan konteksnya memperlihatkan penyingkiran hakhak rakyat banyak. Apa yang kita saksikan sekarang ini, good governance merupakan teknologi mendisiplinkan demokrasi melalui kerangka hukum untuk pembangunan. Uniknya, teknologi dipergunakan secara latah baik bagi kalangan pemerintahan itu sendiri maupun di luar pemerintahan, seperti organisasi nonpemerintah, pusat studi kampus, jurnalis dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Teknologi transplantasi gagasan good governance kian mulus disebabkan persinggungan keinginan perubahan dalam konteks reformasi tidak bisa dijelaskan dengan gampang, mana yang terbilang 'baik' dan mana yang terbilang 'buruk', karena teknologi wacana ini memberikan perangkap di segala lini untuk mengerucut pada proses-proses liberalisasi pasar. Di kalangan intelektual kampus, barangkali memang good governance telah banyak diajarkan melalui diktat-diktat perkuliahan (utamanya kajian ketatapemerintahan dan ketatanegaraan), karena tidak sedikit akademisi dan pusatpusat studi di perguruan tinggi yang penuh dengan kesadaran mentransmisikan gagasan neo-liberalisme ketatanegaraan melalui good governance Dengan perspektif Derrida tentang 'difference', good governance yang dilanggamkan oleh sejumlah pihak nampak seragam, tetapi agenda-agenda secara substansi dibaliknya sungguh berbeda, baik secara historis, konseptual, prinsip, dan narasinarasinya. Tentunya, ketika memperbincangkan konsepsi dominan, wacana Bank Dunia lah yang paling kuat dan berpengaruh untuk lebih bisa menancap pada disain kebijakan pemerintahan, termasuk pembaruan hukum dalam konteks ketatanegaraan. Kedua, teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan good governance juga mendasarkan pada strategi mistifikasi kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak berimbang. Bank Dunia tidak bekerja sendiri di Indonesia, is melibatkan pekerja-pekerja wacana yang memuluskan proyek-proyek pembaruan. Bantuan hukum dalam rangka pengurangan kemiskinan yang digencarkan Bank Dunia (melalui Justice for the Poor), juga digerojok dengan jumlah dana besar agar mesin promosi hak asasi manusia, anti korupsi, demokrasi, rule of law, partisipasi, dan lain sebagainya, kelihatan sungguh-sungguh ada dan bekerja, telah melengkapi wacana paradigma hak asasi manusia ramah pasar. Situasi pemiskinan struktural yang diakibatkan proyek Bank Dunia, seperti kebijakan fleksibilitas buruh dengan - salah satunya - hadirnya PHI yang 28 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia menyakitkan bagi buruh untuk beracara di peradilan, proyek privatisasi, dan komersialisasi, tidaklah menjadi agenda bagi proponen neo-liberal. Dalam konteks inilah, mistifikasi wacana dan mesin institusional merupakan teknologi rasional yang secara sistematik memproduksi konsep `kebenaran dan pengetahuan' good governance, merupakan cara menghaluskan penindasan neoliberal. Ketiga, teknologi perundangan yang dibingkai dalam wacana good governance, dengan menggunakan doktrin rule of law sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, dipergunakan untuk membenarkan imperialisme pasar. Good governance merupakan alat canggih menstipulasi mekanisme perubahan hukum dan institusi melalui kerangka hukum untuk pembangunan sebagai bentuk penjaminan kepentingan korporasi dan pemodal. Secara ideologi, promosi prinsipprinsip liberalisasi pasar jauh lebih kuat dibandingkan perlindungan bagi rakyat miskin, dan hal ini sangat jelas terlihat dari upaya sistematik menarik peran-peran negara agar 'sumberdaya dan pengelolaannya lebih efisien'. Teknologi ini memperlihatkan dua hal: (i) good governance absen dalam upaya pemajuan hak asasi manusia, dan tidak segan-segan menggerogotinya dan mensubversinya dalam bentuk-bentuk kebijakan payung (semacam 'kerangka hukum untuk pembangunan'). (ii) good governance secara paradigmatik memindahkan peranperan negara ke swasta atau privat, sehingga is memperlihatkan jalur yang berbeda dengan aspirasi hak asasi manusia, dan sekaligus membajak jalur yang ada untuk kian melemahkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Inilah apa yang publik percayai tentang kebaikan-kebaikan dalam good governance, yakni good for governing neoliberal performance.' Bila secara sistematik dilakukan dengan teknologi pembenaran melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, maka telah terang bahwa good governance yang sangat menekankan proseduralisme melahirkan proses-proses pelanggaran hak asasi manusia yang difasilitasi oleh hukum yang ada atau dibentuknya (legalized violations of human rights). Dengan mitos ketatanegaraan (dan mantramantranya) good governance yang mengusung agenda-agenda pembaruan, menjelaskan pada kita bahwa hukum ditempatkan sekadar alat kekerasan dan sekaligus pelumas menuju mekanisme pasar bebas. Sebagai kesimpulan, sekaligus peringatan, bahwa good governance sebagai teknologi neoliberal telah benar-benar rapi disiapkan untuk meluruhkan kedaulatan rakyat melalui pintu pembaruan ketatanegaraan Indonesia. Pintu itu memang tidak 100 persen dipaksakan untuk dibuka, melainkan teknokrat liberal sendirilah dari produk rezim reformasi yang menawarkan diri dan bahkan mengajak seisi rumah untuk bermantra membukanya. 6. Penjelasan Sosio-Legal, Rengkuhan `Kenikmatan' dalam studi hukum Melalui studi sosio-legal, memang terjelaskan bahwa telah terjadi perubahan yang cukup banyak termasuk lompatan-lompatan pembentukan dan kerja kelembagaan negara yang kian melengkapi percaturan politik kenegaraan Indonesia. Proyek-proyek hukum dilakukan secara serentak, mulai dari upaya 29 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 pembaruan hukum, pembaruan peradilan, dan pembaruan lembaga-lembaga negara lainnya Dari sudut pandang political economy of law, nampak bahwa bagi Bank Dunia, hukum dan implementasinya dilihat sebagai faktor-faktor penting untuk memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem pasar bebas, salah satu elemen prinsip good governance adalah 'legal framework for development' (kerangka perundangundangan untuk pembangunan) (World Bank 1992). Dalam kerangka perundangan yang demikian, rule of law adalah konsep utama yang secara instrumental dan substansial penting, karena is mengkonsentrasikan pada keadilan (justice), kejujuran (fairness) dan kebebasan (liberty). Bank Dunia menegaskan suatu sistem hukum yang 'fair', yang kondusif untuk menyeimbangkan pembangunan (World Bank 1992: 29-30). Ini sebabnya, tidak terlampau mengejutkan, perspektif Bank Dunia dalam good governance terkait utamanya dengan kebutuhan-kebutuhan perundangan bagi aktor-aktor komersial dalam pasar (LCHR 1993: 53). Pendapat cukup kritis dilontarkan dalam menganalisis hubungan antara rule of law dan kerangka perundangan untuk pembangunan dibawah agenda agenda good governance telah ditulis oleh Tsuma (1999). Menurutnya, Bank Dunia memulai mengarahkan proyek pembaruan hukum dalam 1990an ketika good governance menjadi bagian dari agenda pembangunan (World Bank 1992; 1995a). Kerangka perundangan untuk pembangunan ini sesungguhnya merupakan evolusi pro ekproyek Bank Dunia, ketika Bank Dunia telah mempromosikan good governance sebagai sinonim dengan suara pengelolaan pembangunan (World Bank 1992: 1; Tshuma 1999: 79). Ini disebabkan Bank Dunia meletakkan doktrin rule of law sebagai suatu prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Bila kita lihat lebih jauh, perspektif rule of law dengan memperkuat prosedural dan institusional semata, dalam rangka menjamin stabilitas dan predikbilitas yang menjadi elemen mendasar suatu iklim usaha, adalah suatu perspektif yang lebih dipengaruhi oleh model Weberian dalam hukum. Weber (1978: 24-26) mengidentifikasi 4 jalan dalam orientasi aksi sosial: rasional secara instrumen, rasional nilai, memiliki daya pengaruh, dan tradisional. Ia telah mengargumentasikan bahwa prediktabilitas dan perhitungan dalam sistem perundangan adalah penting bagi pembangunan kapitalis. Rule of law sebagai prasyarat untuk liberalisme kapital adalah konversi segala bentuk produksi buruh, tanah dan modal — ke dalam komoditas-komoditas yang memiliki nilai daya tukar mereka dalam pasar (Tshuma 1999: 85). Dalam hal ini, konversi kapitalistik berarti proses transformasi ke dalam komoditas-komoditas yang menggunakan kekuatan paksa negara untuk merampas hak-hak rakyat dalam jumlah besar. Serupa dengan hal tersebut, Polanyi (1944) telah lama menekankan bahwa transformasi memiliki konsekuensi traumatik bagi mereka yang dirampas alat-alat produksinya serta mereka yang secara konsekuensi dipaksa untuk menjual tenaganya sebagai buruh hanya untuk bertahan hidup (Polanyi, dalam Tshuma 1999: 85). Dalam konteks Indonesia, tekanan disain ketatanegaraan neo-liberal sangat jelas terlihat ketika upaya pembaruan hukum tidak meletakkan arah perubahannya 30 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia pada sistem yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak, melainkan lebih menuruti kepentingan atau selera pasar dalam penciptaan iklim usaha. Dalam soal pembaruan kelembagaan negara, hal ini bisa dicontohkan pada pembentukan institusi peradilan khusus bagi buruh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pembentukan mekanisme peradilan barn ini merupakan bagian dari proyek pembaruan peradilan (judicial reform) yang disponsori Bank Dunia dan bertujuan untuk sekadar meningkatkan `wajah' perekonomian suatu bangsa. Sedangkan dalam soal pembaruan peraturan perundang-undangan, banyak kasus yang bisa dicontohkan, seperti lahirnya Undang-Undang Sumberdaya Air (UU Nomor 7 Tahun 2004), Undang-Undang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007), Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003). Bagi Bank Dunia, proyek pembaruan peradilan adalah relevan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dan ini merupakan kunci sukses strategi peminjaman uang Bank pada suatu negara (Shihata 1995: 170; Armstrong 1998). Singkatnya, proyek pembaruan peradilan dilihat sebagai bagian penting upaya membuat sistem perundangan di negara berkembang dan selatan serta negara dengan ekonomi transisi lebih ramah pasar. Dalam implementasinya, upaya pembaruan ini dilakukan dengan segala bentuk cara mulai dari proses perencanaan dan perancangan kebijakan, merevisinya, mengajarkannya kepada menteri yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan dan mengajaknya untuk berfikir lebih strategis dalam mendorong liberalisasi pasar. Sebagai suatu mesin perundangan, is meyakinkan adanya kompetensi, etika, dan jaminan digaji secara profesional bagi mereka yang membentuk perundangan yang secara baik mendisain promosi aktifitas komersial (Posner 1998: 1; Severino 1999). Sejak 1994, Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika (Inter-American Development Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) telah menyetujui dan mengucurkan pinjaman bagi proyek pembaruan peradilan sebesar US$ 500 juta di 26 negara (Armstrong 1998). Good governance dalam konsepnya yang demikian, memperlihatkan hubungan sangat erat antara upaya-upaya pembaruan hukum (teanasuk pembaruan peradilan) dengan bagaimana menciptakan sistem keuangan yang `sehat' bagi parsyarat liberalisasi pasar. Ia diupayakan untuk menjamin, bukan pada hak-hak masyarakat banyak, melainkan jaminan bagi pemodal yang melakukan investasi dan menggerakkan sumber dayanya dalam suatu mekanisme yang benar-benar efisien. Dalam konteks ini, kerangka hukum ditujukan untuk meyakinkan adanya jaminan hak-hak para kreditor dan bekerjanya fungsi peradilan untuk menegakkannya, arus informasi yang lebih bertanggung jawab, peraturan yang lebih kuat dan independen, khususnya bagi supervisi lembagalembaga keuangan (World Bank 2005: 8). Terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, sungguh bukan hal yang susah untuk diamati sebagai kepentingan neo-liberal yang dimainkan Bank Dunia, karena sejak awal Bank Dunia telah mendorong negara-negara yang berhutang untuk membuat aturan-aturan dan mekanisme hukum barn. Tidak saja 31 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 pada hukum perburuhan saja, banyak kebijakan peraturan barn yang terkait semacam peraturan investasi dan perdagangan, peraturan anti-korupsi, dan pembentukan peradilan usaha (niaga) yang kesemuanya ditempatkan dalam rangka menjalankan mesin legislasi bagi efektifitas pengucuran utang sekaligus meminimalisir resiko atau ketiadaan jaminan hak-hak atas kekayaan. Sekali lagi, good governance lebih bertumpu pada disain substantif kerangka hukum untuk (sekadar) liberalisasi pasar. Faktanya, justru berbahaya dan mensubordinasi hak asasi manusia. Dengan hasil penelitian yang demikian, tentu terasa `kenikmatan' suatu studi yang berada dalam sisi lain suatu mainstream yang memandang good governance sebagai suatu hal yang baik atau tak bermasalah. Secara personal, tak hanya merasakan berada di sisi lain, tetapi sekaligus memahami hukum dan segala konteks, implementasi, strategi transmisi maupun injeksi, serta kontroversi dibaliknya. Tentu saja, temuan itu bisa jadi tak (mudah) populer di kalangan akademisi hukum, tetapi setidaknya, hasil kajian ini seolah menjadi catatan kaki' dari setiap norma, kebijakan, ketentuan beserta realitasnya soal good governance. DAFTAR PUSTAKA Abrahamsen, Rita (2000) Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa. New York : Zed Books. Abrahamsen, Rita (2004) "The Power of Partnership in Global Governance". Third World Quarterly, Vol 25, No. 8, 1453-1467, 2004. Armstrong, Patricia (1998) Selected World Bank, Judicial and/or Legal Reform Projects. New York: Lawyer's Committee of Human Rights. Bello, Walden (2002) Deglobalization: Ideas for a New World Economy. London: Zed Books. Bello, Walden (2005c) Dilemmas of Domination, The Unmaking of the American Empire. New York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company. Bendana, Alejandro (2004) "Good Governance" and the MDGs: Contradictory or Complementary", Paper presented at Institute for Global Network, Information and Studies (IGNIS) Conference, Oslo, 20 September 2004. Gathii, James Thuo (1998) "Representations of Africa on Good Governance Discourse: Policing and Containing Dissidence to Neo-Liberalism", Third World Legal Studies, 65, 1998-1999. George, Susan (1995) "The World Bank and Its Concept of Good Governance", The Democratization of Disempowerment, The Problem of Democracy in the Third World. London: Pluto Press. Hosen, Nadirsyah (2003) Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (19981999). PhD thesis, Faculty of Law, University of Wollongong. LCHR/Lawyers Committee For Human Rights (1993) The World Bank: Governance and Human Rights. New York: Lawyers Committee For Human Rights. 32 Good Governance dan Pembaruan Hukum di Indonesia Parasuraman, S et. al. (2004) Good Governance: Resource Book. Bangalore: Books for Change-ActionAid. Partnership Initiatives (2002) Good Governance in Sustainable Development (http ://webapp s 01 .un. org/dsd/p artnership s/public/partnership s/228 .html) (diakses tanggal 16/6/2006). Pieterse, Jan Naderveen (2004), Globalization or Empire? New York: Routledge. Posner, Richard A (1998) "Creating A Legal Framework for Economic Development", The World Bank Research Observer, Vol. 13, No. 1 (February 1998), p. 1-11. Quadir, Fahimul, Sandra J. Maclean, and Timothy M. Shaw (2001) "Pluralism and The Changing Global Political Economy: Ethnicities in Crises of Governance in Asia and Africa", in Crises of Governance in Asia and Africa, The International Political Economy of New Regionalisms Series. Burlington: Ashgate. Robinson, Richard (2004) "Neo-Liberalism and The Future World: Markets and The End of Politics", Inaugural address as Professor of Political Economy, delivered on 5 February 2004 at ISS/Institute Social Studies, The Hague, Netherlands. Selznick, Philip (1969) Law, Society, and Industrial Justice. New York: Russel Sage Foundation. Severino, Jean-Michel (1999) Remarks to the Jakarta Capital Markets Conference, Vice President, East Asia and Pacific The World Bank, Jakarta, August 24, 1999 Shihata, Ibrahim FI. (1995) The World Bank in Changing World: Selected Essays and Lectures. Vol. 2. The Hague: The Martinus Nijhoff Publishers. Soekarwo (2005) Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PrinsipPrinsip Good Financial Governance. Surabaya: Airlangga University Press. Tshuma, Lawrence (1999) "The Political Economy of The World Bank's Legal Framework for Economic Development", Socio and Legal Studies, Vol. 8 (1), 75-96, New Delhi: Sage Publication. Weber, Max (1978) Economic and Society: Volume 1 and 2. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. Wijoyo, Suparto (2005) Otoda dari Mana Dimulai? Surabaya: Airlangga University Press. Winters, Jeffrey A (1999) 'Criminal Debt', a paper for Conference: Reinventing the World Bank: Opportunities and Challenges for the 21' Century, 14-16 Mei 1999, Northwestern University, Illinois, US. Winters, Jeffrey A (2002) 'Criminal Debt', in Reinventing the World Bank, Jonathan R. Pincus and Jeffrey A. Winters. Ithaca NY and London: Corenll University Press. Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2006) "What's Wrong With 'Good Governance'? A Human Rights Perspective on Governance Reform in Indonesia." Paper presented for The 1" Southeast Asian Studies project of 33 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 2006 on the topic "Indonesian Future in 2006", organized by the Southeast Asian Studies Program (SEAS) of the Liberal Arts Faculty of the Thammasat University, Thailand, 20th January 2006. Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007) Good Governance and Legal Reform in Indonesia. Bangkok: OHRSD Mahidol University. World Bank (1983) World Development Report 1983. Washington: World Bank. World Bank (1989) Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington: World Bank. World Bank (1992) Governance and Development. Washington: The World Bank. World Bank (1994) Governance: The World Bank's Experience. Washington: The World Bank. World Bank (2002) "Module I: Introduction to Governance", Youth for Good Governance, Distance Learning Program. (http://extsearch. worldbank.org/servlet/SiteSearchServlet?q—Governance%20Training%20 Youth%20for%20Good%20Governance%20) (accessed on 14/5/2006). World Bank (2005) OED Review of Bank Assistance For Financial Sector Reform, Country Evaluation and Regional Relations-Operation Operational Development, July 22, 2005, Report No. 33030. 34 TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERPAJAKAN Muhammad Djafar Saidi Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Sul-Sel Abstrak Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya din sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Berhubung karena kaidah hukum dalam UUKUP memberikan wewenang luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak mewujudkannya. Oleh karena itu, kaidah hukum dalam UUKUP memerlukan penataan kembali untuk mencegah tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Korupsi, Perpajakan Abstract Implementation of the tax law in casu UUKUP aims to educate taxpayers fulfill their rights and duties, but tax officials and tax officials to enrich themselves abused in the form of committing corruption in the field of taxation. Since the rule of law because of the tremendous UUKUP authorizes the tax authorities that tax officials to make it happen. Therefore, the rule of law in UUKUP require realignment to prevent corruption in the field of taxation. Keywords : Crime, Corruption, Taxation A. Pendahuluan Ketergantungan negara dari pajak sebagai sumber pendapatan negara tidak boleh dipungkiri lagi. Terlihat pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tiap-tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dilandasi pemikiran penyusun Konstitusi yang lebih memprioritaskan pajak daripada pungutan yangbersifat memaksa lainnya. Awalnya pajak dalam Konstitusi diatur pada Pasal 23ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan : "segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Kaidah hukum ini mengalami amandemen berdasarkan kepentingan negara terhadap sumber pendapatan negara. Amandemen kaidah hukum, tergambar pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan "pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak merupakan energi yang dibutuhkan oleh negara dalam kerangka kelangsungan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berperan dan merupakan unsur terpenting keberadaan dan kelangsungan berdirinya negara hukum Indonesia. Presiden sebagai kepala Pemerintahan Negara, wajib Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 melakukan penataan terhadap "Institusi dan aparaturnya" yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pajak agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berhubung karena, pajak tidak sekadar menunjang hak budget bagi negara melainkan boleh dijadikan sebagai instrumen yang mengatur perekonomian untuk melindungi produk dalam negeri. Pelanggaran hukum terhadap pengelolaan pajak, berkaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Kelanjutan pelaksanaan UUKUP boleh terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Hal ini didasarkan bahwa UUKUP berfokus pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang wajib ditaati oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak dalam kerangka penegakan hukum pajak. Penegakan hukum pajak tidak hanya terfokus pada peningkatan pendapatan negara dan pengaturan perekonomian, melainkan berupaya untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum pajak. Pelanggaran hukum pajak boleh terjadi karena dilakukan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Bentuk pelanggaran hukum pajak dapat berupa "tidak melakukan perbuatan" atau "melakukan perbuatan" yang bertentangan dengan hukum pajak. Misalnya, perbuatan melawan hukum (onrecthtmatige overheidsdaad), penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau kesewenang-wenangan (daad van willekeur). B. Tindak Pidana Pajak Suatu penegasan yang wajib dijadikan pegangan untuk memahami tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, bahwa tindak pidana korupsi tersebut bukan merupakan tindak pidana pajak. Oleh karena, tindak pidana pajak diatur secara tegas dalam UUKUP. Sementara itu, tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam UUPTPK. Akan tetapi, keduanya merupakan tindak pidana khusus karena berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana umum. Walaupun tindak pidana pajak merupakan tindak pidana khusus. Akan tetapi, perlakukan tidak sama dengan tindak pidana korupsi yang memeliki sifat luar biasa "extra ordinary crime" sehingga memerlukan penyelesaian secara luar biasa pula. Hal ini tidak terdapat dalam tindak pidana pajak karena terikat pada asas hukum "ultimun remedium" yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana wajib dilakukan pada tahap terakhir. 36 Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Gambaran umum mengenai tindak pidana pajak sebagaimana diatur dalam UUKUP yang dikemukakan oleh Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar (2012; 18-136) adalah sebagai berikut; 1. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak a. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya; b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; c. Pemalsuan surat pemberitahuan; d. Menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak; e. Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak; f. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak; g. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak; h. Menolak untuk diperiksa; i. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain; j. Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan di Indonesia; k. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; 1. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan; m. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut; n. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak; o. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; p. Tidak memberi keterangan atau bukti; q. Menghalangi atau mempersulit penyidikan; r. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi; s. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain; t. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan; u. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan. 2. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pegawai Pajak a. Menghitung atau menetapkan pajak; b. Bertindak di luar kewenangan; c. Melakukan pemerasan dan pengancaman; d. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pejabat Pajak a. Tidak menenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak; b. Tidak dipenuhi kewajiban merahasiakan rahasia wajib pajak. 4. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Pihak Ketiga a. Menyuruh melakukan (Doenplegen); b. Turut melakukan (Medeplegen); c. Menganjurkan melakukan (Uitlokking); d. Membantu melakukan (Medeplichtigheid). 37 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Optimalisasi penanganan tindak pidana pajak membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum pajak dan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan lembaga penegak hukum pajak lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan pihak kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaaan Agung Republik Indonesia. Substansi yang termuat dalam nota kesepahaman tersebut, meliputi; a. kerjasama penyidikan pajak, pengamanan kegiatan dan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, b. Kerjasama dalam proses penuntutan dan penindakan perkara tindak pidana pajak, dan c. Kerjasama dalam pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam jangka waktu empat tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2009 sampai tahun 2012, jumlah kasus tindak pidana pajak yang selesai dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelaku tindak pidana pajak selama empat tahun terakhir dilakukan oleh 68 wajib pajak badan, 14 wajib pajak bendahara, dan 10 wajib pajak orang pribadi, yang didominasi oleh kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan kasus bendaharawan. Sementara itu, jumlah kerugian pada pendapatan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp.1.13 trilyun. Perkembangan selanjutnya, ternyata sembilan puluh dua kasus telah dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan. Kemudian, enam puluh sembilan kasus tindak pidana pajak telah divonis oleh pengadilan dengan putusan berupa hukuman penjara dan denda pidana hampir sebesar Rp.4,3 trilyun. Tindak pidana pajak yang sangat memperoleh perhatian di masyarakat adalah kasus Asian Agri yang diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp.1.25 trilyun. Tindak pidana pajak tersebut telah divonis oleh Mahkamah Agung dengan putusan dua tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda pidana sebesar lebih dari Rp.2.5 trilyun. Pada awalnya tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Asian Agri telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tahap banding, ternyata vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan oleh vonis Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Beberapa tindak pidana pajak yang dikategorikan sebagai kasus besar lain (di luar kasus Asian Agri) yang telah divonis pengadilan selama empat tahun terkahir, yaitu kasus Sulasindo Niagatama dan kasus Sumber Tani Niaga. Kasus Sulasindo Niagatama diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari Rp.27 milyar. Kasus ini telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara dua tahun dan denda pidana sebesar Rp.336 milyar. Sementara itu, kasus Sumber Tani Niaga diperkirakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara hampir 38 Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Rp.77 milyar. Kasus ini telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman penjara dua tahun dan denda pidana sebesar lebih dari Rp.306 milyar. Pada tahun 2013 diharapkan pengadilan dapat mengadili dan memutus terhadap dua puluh tiga kasus tindak pidana pajak. Harapan itu didasarkan bahwa kasus tindak pidana pajak tersebut telah berada pada posisi berkas P-21. Kasus tindak pidana pajak tersebut berasal dari tahun 2010 sampai tahun 2012 yang belum dapat diadili dan divonis oleh pengadilan dalam wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. C. Tindak Pidana Korupsi Berkaitan dengan Pajak Korupsi merupakan kajian ilmu hukum, tidak hanya berintegrasi pada hukum pidana melainkan berintegrasi pula dengan hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, dan hukum pajak. Walaupun demikian, istilah "korupsi" pertama kali diperkenalkan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Prof Dr. Elwi Danil, SH,MH (2012;5) bahwa dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan isitilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatanperbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi. Korupsi pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang memiliki akibat hukum berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang melaksanakan fungsi negara maupun pihak partikulir (swasta) yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi boleh terjadi dari segala aspek berbangsa dan bernegara yang memperoleh legitimasi hukum positif. Tindak pidana korupsi dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan, tergolong sebagai bentuk tindak pidana yang luar biasa sehingga penanganannya hams dilakukan secara khusus pula. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran tindak pidana korupsi hams disambut dengan prosedur hukum yang berbeda dengan tindak pidana umum. Selama ini penanganan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan telah dilakukan secara maksimal dengan tetap berada dalam koridor hukum positif. Kenyataannya, tindak pidana korupsi bahkan mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kebutuhan, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan institusi dalam menyelengarakan fungsi negara. Meskipun telah ada UUPTPK, tetapi undang-undang ini hanya memuat substansi hukum dengan cara bagaimana memberantas tindak pidana korupsi. Lain perkataan, UUPTPK menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif dan sifat preventif terhadap tindak pidana korupsi dikesampingkan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada humf b UUPTPK yang menegaskan "bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, 39 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, …………… dst". Oleh karena itu, paradigma UUPTPK ke depan memerlukan pengkajian secara utuh menyeluruh sehingga dapat memiliki kemanfaatan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dalam negara hukum Indonesia. UUPTPK dan UUKUP merupakan dua bentuk undang-undang dengan substansi hukum yang berbeda serta digunakan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. UUPTPK memuat substansi hukum dengan cara bagaimana memberantas tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maupun oleh partikulir yang memiliki keterkaitan dengan fungsi negara. Sementara itu, UUKUP memuat substansi hukum berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi pegangan oleh pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Dengasn demikian, penerapan kaidah hukum yang termuat dalam UUPTPK dan UUKUP diharapkan dapat bersinergik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan. Penerapan UUKUP yang bermuara kepada tindak pidana, tidak hanya tertuju pada tindak pidana pajak melainkan dapat pula tertuju pada tindak pidana korupsi. Ketika dilaksanakan UUKUP dan menimbulkan tindak pidana korupsi maka tindak pidana itu disebut sebagai "tindak pidana korupsi di bidang perpajakan". Modus operandi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara, suap, penggelapan, pemerasan dan pemberian. Sementara itu, subjek hukum yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi pegawai pajak, pejabat pajak, dan wajib pajak. Ketiga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada perlakuan terhadap UUKUP sehingga tidak melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pajak. Praktek selama ini, berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak dan pejabat pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut; 1. Gayus HP Tambunan (Pegawai Ditjen Pajak) dengan modus operandi menyalahgunakan wewenang pada saat menangani keberatan pajak Rp.570,92 juta dan memiliki rekening dengan dana Rp.25 milyar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya, karena itu dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Januari 2011. 2. Bahasyim Assifie (Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) dengan modus operandi berupa gratifikasi Rp.1 milyar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartanya Rp.60.82 milyar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp.70 milliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, dihukum dengan hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Pebruari 2011. 3. Dhana Widyatmika (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak) dengan modus 40 Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan 4. 5. 6. operandi menerima gratifikasi Rp.2.75 milyar dari PT. Mutiara Virgo. Memiliki 12 rekening di tujuh bank dengan aliran dana hingga Rp.97 milliar pada salah satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Oleh karena, dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tanggal 9 November 2012. Tommy Hindratno (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan modus operandi menerima Rp280 juta, terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah makan di Tebet Jakarta. Uang suap Rp280 juta dibungkus dalam amplop coklat. Oleh karena itu, dihukum dengan hukuman penjara 3,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tanggal 18 Pebruari 2013. Pargono Riyadi (Penyidik pegawai negeri sipil di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat) diduga melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir. Kurir menyerahkan uang Rp.25 juta yang dibungkus tas plastik di lorong stasiun. Ditangkap oleh KPK di Jakarta, tanggal 9 April 2013. Muhammad Dian Irwan Nugishira dan Eko Darmayanto (keduanya pemeriksa dan penyidik pajak pada Kantor Pajak Jakarta Timur). Menerima suap 300.000 dollar Singapura (sekitar Rp.2,3 milyar) diduga berasal dari wajib pajak korporasi (perusahaan baja) The Master Steel yang beralamat di Jalan Raya Bekasi 21, Jakarta Timur. Ditangkap oleh KPK di terminal 3 Bandara Sukarno-Hatta, tanggal 15 Mei 2013. Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pajak tersebut, tidak terlepas dari tiga faktor yang mendukungnya, yaitu: 1. Substansi hukum dalam UUKUP memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi; 2. Meskipun UUKUP yang bermula dari tahun 1983, telah beberapa kali diubah, dan terakhir pada tahun 2007, ternyata masih memiliki kaidah hukum yang memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, kaidah hukum yang memberi hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Atau, kaidah hukum yang berkaitan dengan keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (force majeur). Serta masih banyak kaidah hukum lainnya yang memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk dilakukan penataan kembali agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi. Pengawasan oleh atasan tidak terlaksana atau kurang terlaksana; Suatu kewajiban hukum yang melekat pada diri seorang atasan adalah melakukan pengawasan kepada bawahannya. Pengawasan itu wajib dilakukan terhadap bawahannya yang tertuju pada kinerja dan tingkah lakunya. Ketika pengawasan itu tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sehingga bawahannya melakukan tindak pidana korupsi maka atasan tersebut wajib dikenakan sanksi administrasi. 41 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 3. Adanya kerjasama pelaku dengan atasan yang membawahinya; Kerjasama atasan dengan bawahan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang terbaik kepada negara merupakan suatu hal yang memerlukan penghargaan. Sebaliknya, bila kerjasama itu mengarah kepada tindak pidana korupsi, berarti atasan dan bawahan melakukan kerjasama untuk melanggar sumpah atau janji pada saat diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pada saat memangku jabatan yang dipangkunya. Oleh karena itu, keduanya wajib diberhentikan menjadi pegawai negeri sipil sebagai bentuk pengenaan sanksi administratif yang sifatnya berat. 4. Karakter dari pegawai pajak dan pejabat pajak; Pada hakikatnya, karakter seseorang sangat berperan untuk dijadikan alat ukur dalam kerangka menilai pengabdiannya kepada negara. Ketika karakter dari pegawai pajak atau pejabat pajak sangat mendukung untuk berkarir maka pekerjaan yang ditekuni tersebut akan menghasilkan yang terbaik. Sebaliknya, bila karakter dari pegawai pajak dan pejabat pajak sangat diragukan pada saat melakukan atau menjabat suatu jabatan maka jabatan yang dipangkunya dapat dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, terlebih dahulu ditempuh keempat hal tersebut. Berhubung karena keempat hal itu tidak terpisah satu dengan lainnya, berarti memerlukan pemikiran dari pakar hukum pajak dan birokrat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama ini, tidak terjalin kerjasama antara pakar hukum pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi dengan birokrat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan setiap saat dapat dilakukan agar negara dapat segera mewujudkan fungsinya yang utama yaitu mewujudkan "masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam keadilan" yang berujung pada penaatan hukum pajak. D. Kesimpulan Pada bagian ini, dikemukakan beberapa hal yang sangat mendasar yang terkait dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum pajak dapat berdampak kepada tindak pidana pajak dan bahkan tindak pidana korupsi. Namun, tindak pidana pajak tidak memiliki sifat yang luar biasa sehingga penanganannya juga tidak dilakukan secara luar biasa. Berbeda dengan Tindak pidana Korupsi di bidang perpajakan memiliki sifat yang luar biasa sehingga penanganannya hams dilakukan secara luar biasa. Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, tidak terlepas dari empat faktor sebagai penyebabnya. Faktor penyebab yang lebih dominan adalah kaidah hukum UUKUP yang memberikan kewenangan luar biasa kepada pejabat pajak sehingga pegawai pajak ikut berperan mewujudkannya. Sementara faktor lain, berupa pengawasan, kerjasama, dan karakter hanya merupakan faktor pendukung. Oleh karena itu, perlu penataan kembali UUKUP yang mengarah kepada pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. 42 Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 2012; Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Cetakan ke-5, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta; Elwi Danil, 2012; Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Penerapannya, Cetakan ke2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta; Muhammad Djafar Saidi, 2011; Pembaruan Hukum Pajak, Cetakan ke-3, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta; Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar, 2012; Kejahatan Di Bidang Perpajakan, Cetakan ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta; Santoso Brotodihardjo, 1995; Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit PT Eresco, Bandung; Andi Zainal Abidin Farid, 2007; Hukum Pidana I, Cetakan ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta; …………., Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, 2006; Edisi Kedua Cetakan Kedua, Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. 43 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 44 ISSN : 2303-3274 TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM The Compensation Theory in Islamic Law Perspectives Asmuni Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesa Yogyakarta Abstrak Ide Ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi atau daman. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina'iya.h untuk sebutan tanggung jawab pidana. Akan tetapi sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-qz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (baca: daman), dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana (baca: `uqubah diyat, arusy dan lain-lain). Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha' sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. Daman dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut daman al-aqdi, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut daman `udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku. Kata Kunci : Ganti Rugi, Hukum Islam, Perspektif Hukum. Abstract The idea of daman towards both criminal and justice victims, from early time, has been mentioned in the nash of both Al-Quran and Al-Hadith. From the nash, Ulemas have formulated various fiqh forms concerning daman (compensation). In fact, from early time the Islamic Jurists have not applied the terms masuliyah madaniyah for justice responsibility, and masuliyah al ina'iyah for criminal one. However, several thinkers of classical Islamic law mainly al-Qurafi and al- `Iz Ibn Abdi Salam have introduced the term al-jawabir for justice conpensation (read: daman) and al-zawajir for criminal compensation (read: 'uqubah diyat, arus, etc.). Although in its development, up to recent time, Islamic Jurists often use the term masuliyah that is because of the Western work influences. Daman could occur because of deviation on akad (agreement) namely daman al-aqdi, and could happen because of violation namely daman `udwan. In determining the compensation, the esential elements are darar or lost on the victims. Darar could Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 occur on physical, material or things and service aspects; and it could also be on moral and emotional destruction or called darar adabi including name-reputation damage. The standard for the compensation either on quality or quantity must be similar to darar suffered by the victims. Although in certain cases, the multiplying compensation may happen based on the victims' condition. Keywords : Compensation Theory, Islamic Law, Law perspectives A. Pendahuluan Sebelum hadirnya Islam, ide kreatif yang berkaitan dengan pemikiran hukum, sama sekali tidak ditemukan. Perlindungan terhadap hak-hak individu dengan sendirinya terabaikan. Bilapun hendak memperoleh hak-hak individu tersebut, satu-satunya cara adalah melalui kekuatan yang disimbolkan oleh kekuasaan. Hal inilah yang kemudian menjadi hukum. Karena belum adanya aturan yang baku, maka kezaliman dan penindasan merajalela di mana-mana. Permusuhan dan main hakim sendiri menjadi tontonan yang tidak asing lagi. Suku yang lebih kuat akan merasa lebih terhormat dan berbuat semena-mena terhadap suku yang lemah. Dalam situasi yang tidak mengenal "hukum" seperti inilah kemudian turun Al-Qur'an kepada Muhammad Negara Islam pun berdiri bersamaan dengan datangnya agama barn yang komitmen terhadap perintah dan larangan Tuhan (imtisal al-awamir wa ijtinab alnawahi). AlQur'an menegaskan "athi'ulla wa athi'u ar-rasul " (Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya). Posisi dan keberadaan sistem kesukuan yang cenderung tirani dan semenamena, digantikan oleh kekuasaan publik "sulthoh 'arnmah" yang memberlakukan hukum syariah untuk melindungi hak-hak individu masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, bahkan agamanya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah Secara umum, hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua orang diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut dan bekerja secara sungguhsungguh untuk memeliharanya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa: man qotala nafsan bigairi nafsin awu fasddin fi al-ardh fakaannama qotala alnasa jami 'a, juga man qotala mu 'rninan khotho 'an fatahriru roqobatin mu 'rninatin wa diyyatun musallamah ila ahlihi. Al-Qur'an juga mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan berlaku ihsan kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an melarang makan harta orang lain dengan cara yang tidak sah menurut hukum, mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan yang zalim untuk menghilangkan darar pada korban: wa jaz al-'u sayyiatin sayyiatun misluha, juga famani' tada „alaikum fa'tadu „bi misli mani'tada „alaikum. Islam juga meletakkan prinsipprinsip tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain: fakullu nafsin bima kasabat rahinah, juga wa likulli insanin ma kasaba 46 Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam wa `alaihi ma iktasaba, serta wala taziru waziratun wizra ukhra dan prinsip-prinsip lainnya yang belum dikenal oleh sistem hukum Barat kecuali di zaman modern ini. Sunnah Nabi pun muncul untuk memperkuat makna prinsip pertanggungjawaban tersebut. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad bahwa al-muslim akhu almuslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu. Sunah Nabi juga meletakkan pondasi kaidah-kaidah umum yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian (darar) secara mutlak seperti disebutkan oleh hadis Nabi La darara wala diroro. Pada saat haji wada', juga menegaskan dasar-dasar umum untuk kehidupan sosial yang anggun dan bermartabat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Muhammad, beliau mewajibkan daman (ganti rugi) pada perbuatan yang berlatar belakang ta 'addi (pelanggaran terhadap hukum) pada amwal (harta), al-mumtalikat (hak milik), Nabi menegaskan "'ala al-yadi ma akhazat hatta tarudduhu". Bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum tersebut di atas, para fuqaha' memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban (qawa 'id al-mas filiyah). Mereka melakukan identifikasi mana yang masuk dalam kategori khitab al-taklif al-j ina (pidana) yang berimplikasi pada al- `uqubah (hukuman) terhadap pelaku (mukholafatu awamir al-syari' wa ahkamihi), dengan al-taklif bi daman (beban ganti rugi). Dalam hubungan inilah al-Qurafi dan `Izzuddin Ibn Abdi al-Salam masing-masing dalam karya mereka al-Furuq dan al-Qawa 'id al-Ahkam menegaskan dan menjelaskan secara konkret perbedaan antara al-zawajir atau al`uqubat dengan al-jawabir atau damanat.1 Demikian pula pada pasal-pasal lain dalam al-Majallah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perampasan (al-gash), misalnya, dimuat dalam pasal 890912. hukum-hukum yang berkaitan dengan perusakan barang Wan dimuat dalam pasal 912-942. 1 Kenyataan ini kemudian menyimpan pertanyaan akan sumber perundang-undangan Barat yang sesungguhnya ketika membedakan antara al-masuliyah al-jinaiyah (tanggung jawab pidana) dan al-masuliyah al-madaniyah (tanggung jawab perdata), dan antara al-masuliyah altaqshiriyah (tanggung jawab akibat kecerobohan dan kelalaian) dan al-masuliyah al-aqdiyah (tanggung jawab akibat pelanggaran perjanjian kontrak). Adalah sangat tidak mungkin model pembagian ini tanpa dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Meski demikian al-Sanhuri berkeyakinan bahwa sistem hukum Perancis adalah paling awal dalam menjelaskan masuliyah dan macam-macamnya dengan melakukan interpretasi terhadap hukum Romawi. Padahal hukum Romawi tidak melakukan pembagian al-masuliyah secara rinci seperti itu. Inilah yang ditegaskan oleh Sayyid Abdullah Husain ketika menolak pendapat Sanhuri dengan menyatakan: "Pengambilan atau penyaduran dan mazhab Malik bukan dimulai pada tahun 1805, melainkan sejak tahun 200 H. Ketika Islam menguasai Eropa, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, pada saat Eropa secara umum berada dalam kegelapan intelektual." Pada saat itu Islam masuk daratan Eropa dan memerintah penduduknya serta membangun kaidah-kaidah hukum yang adil. Penduduk Eropa berdatangan ke Andalusia semata-mata untuk menimba ilmu pengetahuan. Abdullah Husain juga berpendapat bahwa hukum perdata Perancis yang menjadi sumber berbagai hukum saat ini adalah terambil dari mazhab Malik ibn Anas. Lihat Sayyid Abdullah Husain, 'al-Muqaraniit al-Tasyri'iyah", dalam Muhammad Ahmad Siraj, Daman al- Vdwan fi al-Filth al-Islami (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah bi ahldim al-masuliyah alTaqshiriyah fi al-qanun), al-Muassasah al-Jami'iyyah li al-Dirdsat wa al-Nasyr wa alTauzi', hal. 15. 47 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Tulisan ini tidak bermaksud melakukan perbandingan antara teori daman2 menurut fiqh dan hukum, apalagi melakukan kajian terhadap pengaruh hukum fiqh terhadap sistem hukum Barat terutama hukum Perancis. Tulisan ini hendak mengemukakan teori daman secara umum dan sebagian aplikasinya terhadap tanggung jawab seseorang atas perbuatannya. B. Pengertian Ganti Rugi (Daman) Secara etimologis, daman2 memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus Lisan al-'Arab, Ibnu Manzur menandaskan bahwa semua makna daman terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus al-Muhith3 yang mengartikan daman dengan ganti rugi. Dalam term fiqh, daman juga dimaknai beragam.4 Imam Ghazali,5 misalnya memaknai daman dengan "luzumu rad al-syayy' awu badaluhu bil mitsli awu bil qimati (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya). Al-Hamawy6 pensyarah kitab al-Asybah wa alNaza'ir karya Ibn Nujaim mengatakan bahwa daman adalah 'ibaratun 'an raddi misli awu qimatuhu (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani7 mengatakan bahwa daman adalah `ibaratun 'an garamati al-talif (mengganti barang yang rusak). Majallah al-Ahkam al-Adliyah8 menyebutkan bahwa ganti rugi disesuaikan dengan jenis barang yang rusak (daman huwa i'tha'u misli al-syai' inkana minal misliyat, waqimatuhu inkana minal qimiyat). Apabila jenisnya tergolong almisliyat, maka ganti ruginya dengan barang yang sama (al-misli). Jika barang yang rusak tergolong al-qimiyat, maka nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai jualnya di pasar (qimah).9 Menurut al-Zarqa'10 daman adalah iltizam bi ta 'widhin maliyin 'an darari al-gair. Sedangkan menurut al-Zuhaili daman adalah hua al-iltizam bita 'widhi al-gair „amma lahiqahu min talafi al-mal awu awu ishabatin min dhararin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Dalam fiqh kontemporer istilah ganti rugi (daman) sering digandengkan dengan istilah almasuliyah. Daman sendiri mengandung makna ganti rugi, sedangkan al-masuliyah mengandung makna tanggung jawab. Dasar hukum syar'i tentang daman maupun almasuliyah, antara lain ya aiyuhallaz Ena cimana la tasalit 'an asyyd in tubda lakum tasu'kum (al-Maidah: 101); fas 'al bihi khabira (al-Furqon: 59); inna as-sam'a wa albashara wa al-fu 'dda kullu ulaika kcina anhu masfila (al-Isra': 36). Majduddin al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhit, Kairo: Dar al-Hadis, tt, bagian daman. Definisi daman yang beragam mengarah pada makna menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Karena itu, biasanya daman mengandung tiga masalah pokok, yaitu (1) jaminan atas utang seseorang; (2) jaminan dalam pengadaan barang; dan (3) jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti pengadilan. al-Gazali, al-Wajiz, hal. 1/208. Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawy, Gamzu „Uyuni al-Basha 'ir wa Syarah al-Asybah wa al Naiza 'ir, Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, Cet. 1405 H/1985 M, hal. 2/211. As-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, Mesir: Mustafa al-Babi alHalabi, 1380 H, hal. 5/299. Atasi, Syarah Majallatu al-Ahkam al- Adliyah, dicetak di Hims Suriah, 1352 H. al-Majallah, pasal 416. al-Zarqa', al-Madkhal, hal. 1032, pasal 648. Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam juz awu kulli hadisun hi al-nafsi al-insdniyah awu hi'udhwin minha.11 Baik definisi al-Gazali maupun al-Majallah sama-sama membatasi daman pada tanggung jawab akibat perbuatan yang tergolong ta 'addi seperti merampas atau merusak harta orang lain. Kedua definisi tersebut juga tidak menyentuh daman al-aqdi (ganti rugi yang muncul akibat pelanggaran akad). Pengertian daman seperti ini sudah barang tentu masih kurang karena tidak mengakomodasi seluruh teori daman yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha'. Adapun definisi al-Syaukani, al-Zarqa', dan al-Zuhaili sama-sama berangkat dari darar. Darar-lah yang mewajibkan ganti rugi. Berdasarkan titik tolak ini maka daman mencakup sesuatu yang wajib pada zimmah untuk menghilangkan darar yang muncul akibat pelanggaran pada akad (mukhalafatu aqdin), melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan mafasid. AlBazdawi mengisyaratkan dua macam daman, yaitu daman al-aqdi fasidan kana awu jaizan yajibu bi al-tarodhi, wa daman al-rudwan ya'tamidu awusofal ain12 (ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz (akad sahih) diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang). Hal yang sama juga dilakukan oleh al-Sarakhsi. Ia membedakan antara daman judwan dengan daman al-aqdi (ganti rugi akibat pelanggaran dengan ganti rugi berdasarkan akad).13 Indikasi perbedaan tersebut juga ditunjukkan oleh al-Suyuthi yang merinci sebab-sebab daman menjadi dua yaitu ta' addi dan aqdi.14 Cakupan daman, dengan demikian, meliputi wilayah perdata dan pidana. Sehingga ganti rugi dapat terjadi atas barang yang rusak atau manfaat barang yang hilang, atau luka fisik seseorang sehingga mengakibatkan kerugian, baik total atau sebagian. Dari catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa daman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik darar yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian definisi ini mencakup makna-makna sebagai berikut: a. Obyek wajib daman terletak pada zimmah (perjanjian). Kewajiban daman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan mutasabbib (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, syari' hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan khitab al-targib yang meliputi makruhat dan mandubat. Zimmah menurut bahasa adalah al- `andu 11 12 13 14 Wahbah al-Zuhaily, al-Mas 'uliyah 'an Fi al-Gair, Damaskus: Dar al-Muktabi, Cet. 1, 1416 H/1995 M, hal. 12. Al-Bazdawi, Ushul, hal. 31. Al-Saralchsi, al-Mabsut, Mesir: al-Sa'adah, 1324 H, hal 11/69. Jalaluddin Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Naza 'ir, Beirut: Muassasah al-Kutub alSaqofiyah, Cet. 1, 1415 H/1994 M, hal. 362. 49 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 b. d. e. f. 50 ISSN : 2303-3274 (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' zimmah adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. Ahlu zimmah adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban atas dasar daman berbeda dengan kewajiban atas dasar `uqubah, baik pada karakter maupun tujuannya. Daman ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan `uqubah ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada daman bertujuan untuk mengganti atau menutupi (al-jabru) kerugian pada korban. Sementara `uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (al- zajru). Jadi tujuan yang berorientasi pada aljabru disebut daman. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada al-zajru disebut `uqubah. Sebab-sebab daman adalah adanya unsur ta'addi, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta'addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya hams dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (al-muda)' tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang al-ajir (buruh upahan, orang sewaan) dangan al-musta jir (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. Ta'addi juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (mukhalafatu ahkcim syari'ah) seperti pada kasus perusakan barang perampasan (al-gasb), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihme11). Ta'addi yang mewajibkan daman benar-benar menimbulkan darar (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada daman, karena secara faktual tidak ada darar yang hams digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan daman. Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan daman seperti algasbu (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan hams mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kemgian atau darar juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menumt fuqaha' Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa al-dharar syarthun liwujubi daman (kerugian adalah syarat terhadap kehamsan ganti rugi). Antara ta'addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, darar dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika darar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (muta'addi) sendiri, maka daman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Darar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: laa dharara Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam wa laa dhirara (tidak boleh memgikan diri sendiri dan memgikan orang lain). Tingkat darar diukur berdasarkan `urf (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: yajibu hamlu al-lafzi `ala ma'nahu almuhaddad fi as-syar'i in wujida, wa illa wajaba hamluhu `ala ma'nahu al-`urfi (suatu kehamsan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan `urf). Karena syari' tidak menetapkan makna darar, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada `urf. Dengan demikian, darar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan `urf yang berlaku di tengah masyarakat. g. Kualitas dan kuantitas daman hams seimbang dengan darar. Hal ini sejalan dengan filosofi daman, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional. Penetapan makna demikian sejalan dengan makna darnan15 secara bahasa, yakni ganti mgi. Maksud ganti mgi yaitu penggantian kerugian yang dialami seseorang. Pemaknaan seperti ini juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1248. Dari sini perlu dimengerti bahwa daman dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, temtama menyangkut jaminan harta benda dan nyawa manusia. Maka dari itu, tidak mengherankan bila al-Mawardi mengatakan bahwa daman dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Dengan demikian, daman dapat diterapkan juga dalam masalah jual beli, pinjam meminj am, titipan (al-wadi 'ah), jaminan (rahn), kerj a patungan (qirad/mudharabah), barang temuan (luqathah), peradilan (qadd), hukuman terhadap pembunuhan (qisas), perampasan (gasab), pencurian, dan sebagainya. 15 Dasar legalitas daman antara lain ayat al-Qur'an: famani'tadd `alaikum fa 'tadii bimisli ma i'tadd `alaikum"(al-Baciarah: 194); ayat wa jazeiu sayyiatin sayyiatun mis/uhei(al-Syuro: 40); ayat wa in `aqabtum fa 'aqibei bimisli ma -tiqibtum bihi" (alNahl: 126). Adapun di dalam al-Sunnah disebutkan, antara lain hadis, riwayat Anas berkata: Ahdat ba'dhu azwajin nabi SW ilaihi tha'aman fi qush'atin, fadharahat al-qus 'ata hiyadiha, fa alqat ma fiha, faqdla an-nabi SW: tha'amun bitha 'amin, wa indun bi Main (Riwayat Tirmizi). Juga hadis yang cukup populer 'Ala al-yadi ma akhazat hattil tuaddihi (Riwayat Ahmad). Hadis lairmya, Irma dimdakum wa amwellakum `alaikum haromun kahurmati yaumikum haza, fi syahrikum haza, fi baladikum haza (Bukhari Muslim). Ibn Hazam juga mengatakan bahwa yang sahih adalah bahwa harta yang diharamkan tidak ada kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi terhadapnya, baik di dalam nas ataupun ijma'. Hadis lain yang paling populer adalah la dharara wa la dhireira. Imam al-Kasani berkata, "Diwajibkan ganti rugi pada kasus perampasan dan perusakan (al-gashbu wa al-itlaf), karena semua itu mengandung unsur perbuatan i'tida‟ dan idrar."(Bada'i, hal. VII/165). 51 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 C. Sebab-Sebab Ganti Rugi (Daman)16 Kaum fuqaha' tidak mendiskusikan rukun daman secara sistematis dan terpadu seperti yang dilakukan oleh ahli hukum. Mereka membahasnya secara sporadis di berbagai tempat, antara lain di dalam kitab-kitab al-furu', kaidahkaidah fiqh, dan kitab ushul al-fiqh. Walau begitu, rukun daman sudah tergambar di dalam pemikiran mereka ketika mendiskusikan berbagai kasus hukum fiqh. Dari berbagai konstruksi dan fatwa hukum dalam karya-karya fiqh, dapat disimpulkan bahwa rukun daman adalah khatha', dharar, dan sababiyah. Perbuatan-perbuatan hukum yang mewajibkan daman hampir tidak terbatas jumlahnya. Tetapi secara akumulatif perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan gair masyru 'ah, atau akhtha' atau ta 'ddiyat (delicts, torts, wrongs). Namun untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan, maka para ahli hukum pertama-tama melakukan pembagian terhadap perbuatan prespektif motif dan tujuan pelaku menjadi: akhtha' amdiyah (intekntional torts) dan akhtha' taqshiriyah atau al-ihmal (negligence). Di dalam fiqh, al-akhtha' gair al- `amdiyah dibagi menjadi dua macam yaitu al-khatha' dan ma jara majrahu. Suatu perbuatan yang menjadi tujuan pelaku, namun tidak menghendaki akibatnya disebut al-khatha'. Sedangkan suatu perbuatan dan akibatnya sama-sama tidak dikehendaki oleh pelaku disebut ma jara majra al-khatha'. Yang pasti khatha' amdi sangat berbahaya sehingga di dalam hukum Barat - dengan mengacu kepada istilah hukum Perancis - disebut alkhatha' lei yagtafiru (kesalahan yang tidak dimaafkan).17 16 17 52 Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: ali'tida' dan al-darar. Al-i'tida' adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha' mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab daman ada tiga, yaitu aqad, yad, dan itlaf. Daman pada aqad dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (al- `urf atau al- `aclah) yang berlaku. Sedangkan wadh'u al-yad dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu alyad mu 'tamanah maupun bukan mu 'tamanah. Yad al-mu 'tamanah seperti yad al-wadi' dan al-mudharib, alamil al-musaqi, al-ajir al-khas, al-washi `ala mal al-yatim, hakim dan al-qadhi` al asunduq dan lain-lain. Mereka ini jika melakukan ta 'addi (personal abuse case) atau taqshir dibebani / dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak ada unsur ta 'addi atau taqshir tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong al-aydi al-amcinah (tangan-tangan amanah). Adapun al-yad gairu al-mu 'tamanah yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti alyad al-ba terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau al-musytari setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan ta 'addi terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun aliticif menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. Itlaf biasanya diartikan mendisfungsikan barang. dibagi dua yaitu al-itlaf al-mubasyir (perusakan langsung), dan al-itlaf bi al-tasabbub (perusakan tidak langsung). (Pembahasan tuntas dapat dilihat dalam al-Kasani, al-Badai' dan dalam Majallatu al-Ahkam al- Adliyah pasal 887-888. Siraj, Daman, Ibid. Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam Perbuatan-perbuatan mewajibkan daman, kata al-Qurafi18 adalah dilakukan secara langsung oleh pelaku (al-„udwan bi al-mubasyir), kemudian karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan (al-tasabbub li al-itlaf) pada harta benda misalnya. Singkatnya, sebab-sebab daman adalah al-mubasyir, altasabbub, dan al-itlaf. Kerusakan ini tidak mesti menjadi tujuan dari pelaku (qashdu al-fa'il). Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Adapun kesengajaan (al-. amd) yang mengakibatkan darar atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan darar, tidak menjadi syarat dalam penetapan daman. Karena daman berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup khatha' atau `udwan bukan pada tujuan perbuatan atau niat pelaku. Namun demikian, khatha' yang mengharuskan daman dibedakan dengan khata' yang mengharuskan `uqubah serta khatha' al-akhlaqi (kesalahan secara moral) yang hanya berimplikasi pada dosa. Orang tidur menurut teori ini tidak salah secara moral dan juga tidak berdosa. Dengan demikian kalau dia terbolak balik atau jatuh menimpa sesuatu sehingga menimbulkan kerusakan, dia wajib melakukan daman, tetapi secara etis relegius dia tidak berdosa. Daman tidak terkait dengan al-qasdu dan al-niat. Pendapat ini berdasarkan ijma'. Karena ijma'-lah yang mewajibkan daman bagi seorang anak yang belum dewasa (al-sabiyi), orang gila (al-majnun), orang pelupa (al-nasi), orang tidur (alnaim) dan orang lalai (al-gafil). Daman semata-mata terkait dengan al-asbab (adanya sebab akibat). Atau dengan meminjam istilah imam al-Gazali bahwa alahliyah (cakap hukum) yang menjadi syarat dalam menetapkan daman adalah ahliyatu al-wujub yaitu seseorang dianggap cakap hukum untuk menerima hak, bukan ahliyat al-ada' di mana seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Meski sangat jelas bahwa khatha', ihmal, dan taqshir menjadi syarat wajib daman, namun tim penyusun al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah sepertinya mengabaikan prinsip-prinsip umum daman. Hal itu terbukti bahwa mereka menetapkan unsur kesengajaan (ta'ammud) sebagai syarat daman. Kemungkinan ada dua faktor yang menyebabkan kekeliruan tersebut. Pertama, mengikuti kesalahan yang terdapat dalam karya-karya klasik terutama kitab al-Asybah karya Ibn Nujaim. Kedua, ada kemungkinan mengikuti jejak sebagian fuqaha' Hanafiyah generasi awal yang keliru memahami dan menafsirkan mazhab Abu Hanifah yang menetapkan bahwa penyebab kerusakan dibebani ganti rugi (tadhmin mutasabbib) Imam mazhab sendiri tidak melihat tadhmin mutasabbib kecuali ada unsur kesalahan (al-khatha) yang mirip dengan kesengajaan atau suatu kesalahan yang sangat berlebihan sehingga mendekati atau setidaknya mirip dengan kesengajaan. Terlepas dari apakah ini merupakan kesalahan ilmiah atau kesalahan teknis pengetikan, namun yang pasti kaidah tersebut hares dibaca dalam konteks sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Majma' Damanat.19 18 19 al-Qurafi, al-Furuq, Ibid. al-Bagdadi, Majma' al-Damanat, Mesir: al-Khairiyah, 1388 H, hal. 57. 53 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Kaum fuqaha' tidak menetapkan syarat bahwa orang yang menyebabkan (mutasabbib) kerugian hams sudah mumayyiz, atau memiliki al-idrak (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kewajiban daman. Sehingga seorang anak yang masih usia mumayyiz atau belum, wajib dikenakan daman jika melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lan. Demikian pula al-ma'tuh (orang idiot) dan al-majnun (gila). Karena tujuan dari daman adalah ganti rugi dengan mal, yang pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Hadis tentang diampuni umatku suatu perbuatan karena kelalaian dan kealpaan, tidak menafikan hukum daman ketika terjadi al-taqshir (kecerobohan) dan al-ihmal (kelalaian). Karena yang diampuni adalah dosa atau hukuman pidana, bukan hukuman daman. Hal inilah yang menjadi perhatian para fuqaha'. Seorang faqih Sadru al-Syari'ah menyebutkan bahwa al-khatha' adalah apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu sendiri tidak diniati secara sempurna. Misalnya, orang menembak hewan buruan namun pelurunya nyasar mengenai seseorang sehingga tewas. Di sini terdapat niat atau al-qasdu yang tidak sempurna. Sehubungan dengan ini si pemburu tidak dapat dikenakan qisas karena hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku pidana penuh. Atas dasar ini, is tidak dapat dikenakan kepada orang ma'zur (orang yang dimaafkan). Namun `uzur ini terkait dengan hak-hak hamba sehingga kategori daman-nya adalah daman al- `udwan. D. Macam-macam Khatha' dan Darar Secara teoritis khata' dapat berupa meninggalkan kewajiban yang ditetapkan oleh syariah. Misalnya, seorang ibu meninggalkan anaknya sehingga jatuh. Khata' juga dapat dalam bentuk melakukan perbuatan yang haram. Misalnya, memberikan kesaksian palsu, merampas harta orang lain, merusak atau menyebabkan rusaknya harta. Daman tidak akan berlaku kalau tidak ada unsur khatha'. Dan khatha' tidak akan ada kalau seseorang melakukan suatu perbuatan yang diijinkan oleh syariah (hukum). Sedangkan darar sendiri ada tiga macam, yaitu darar yang berkaitan dengan kehartabendaan; darar yang berkaitan dengan fisik; dan darar yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang atau lembaga. Yang terakhir ini disebut dengan darar adabi. Menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik masuk dalam kategori al-masalih al-daruriyah atau kemaslahatan primer. Namun dari aspek lain, darar dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, darar alyasir (kerugian ringan). Para fuqaha' pada umumnya berpendapat tidak ada daman terhadap darar ini. Menurut hemat penulis, permasalahan ganti rugi terhadap darar yasir bersifat kondisional. Kedua, darar fakhisy (kerugian berat). 54 Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam Sementara kerusakan terhadap harta benda (darar maliyah) dapat digolongkan menjadi kerusakan terhadap benda bergerak (manqulat), benda tidak bergerak ( Vqarat), dan jasa (al-manafi).20 Para fuqaha' sepakat atas daman terhadap kerusakan benda bergerak (karena merampas barang, merusak atau menguranginya, mengubah bentuk barang atau mengeksploitasi pemanfaatannya). Sehubungan dengan daman barang-barang bergerak terdapat dua syarat: Pertama, maliyatu al-manqul (barang bergerak itu betul-betul harta secara syara'). Al-manqulat (bentuk jamak dari al-manqul) yang kehartaannya tidak diakui oleh syara' tidak dapat dilakukan ganti rugi terhadapnya. Itulah sebabnya tidak ada daman dengan merusak bangkai, kulit bangkai, darah dan lain-lain yang pemanfaatannya dilarang oleh syara'. Juga yang tidak dapat dilakukan daman terhadapnya adalah al-mubahat al- `ammah (hak-hak umum) yaitu al-kala' (rumput), al-ma' (air) dan al-nar (api). Itulah sebabnya jika ada seseorang menimba sumur orang lain sampai kering, tidak dikenakan daman. Sebab pemilik sumur, bukan berarti memiliki air, berbeda kalau merampas air dari wadah yang lain. Hukum al-kala' (kecuali kalau dipelihara dan ditanam), dan al-nar sama dengan hukum al-ma'. Kedua, tuqawwimu al-manqul (barang tersebut mengandung nilai ekonomis). al-Taqawwum menurut Ibn Nujaim dapat ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu adanya unsur kehartaan (al-maliyah) dalam suatu barang, dan barang tersebut boleh dimanfaatkan menurut syara'. Adapun barang-barang tetap (al-Vqdrat, immovable property), para fuqaha' bersepakat wajibnya daman terhadapnya apabila merusak keseluruhan, sebagian atau merugikan pemiliknya. Berbeda dengan manafi' terdapat perbedaan pendapat yang berkaitan dengan daman terhadapnya. Perbedaan ini sebagai konsekuensi dari silang pendapat yang terjadi antara fuqaha tentang status kehartaan al-manafi' (maliyatu al-manafi). Fuqaha' Hanafiyah terutama generasi awal tidak menetapkan daman terhadap al-manafi', karena wujudnya yang abstrak, sehingga ia tidak termasuk harta. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha dari berbagai mazhab, termasuk Syiah Imamiyah, menurut mereka daman terhadap almanafi' sesuatu yang wajib. Argumentasi fuqaha' Ahnaf antara lain bahwa al-manafi' tidak mengandung nilai ekonomis. Statusnya sama dengan khamar dan bangkai. Artinya, tidak tergambar pada al-mandfi' mengingat sifatnya yang abstrak. Pendapat ini oleh fuqaha' Hanafiyah generasi mutaakhkhirin dianggap lemah, sehingga mereka mengevaluasi pendapat tersebut dan mengemukakan bahwa adalah bagian dari al-mal (harta). Adapun darar badaniyah meliputi jiwa, anggota badan, atau hilangnya fungsi salah satu anggota badan. Misalnya, hilangnya pendengaran dan penglihatan. 20 Lihat Ibrahim Fadil al-Dabbo, Daman al-Manafi' dirasah muqaranah fi al-filth alislami wa al-qanun al-madani, Amman, Beirut: Dar al-Bayariq, Dar 'Ammar, Cet. I, 1417 H/1997. 55 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Terhadap semua kasus yang berkaitan dengan kerugian fisik seluruh atau sebagiannya, menurut para fuqaha' berlaku hukum daman terhadapnya. E. Menakar Ganti Rugi Tujuan dari pada daman adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita (raf'u al-darar wa izalatuha). Hal ini mencakup dua hal. Pertama ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama balk seseorang. Kedua, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut jawabir al-dharar al-badaniyah mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. Jawabir model ini oleh para fuqaha' disebut dengan diyat (ganti rugi pembunuhan), ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi model ini sering disebut hukumatu 'adl karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil. Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (jawabir al-darar al-maliyah) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu: 1. Jawabir naqdiyah yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (alqimah). 2. Jawabir `ainiyah, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal. Adapun hitungan atau perkiraan (al-taqdir) ganti rugi bisa mengacu pada beberapa model berikut. Pertama, perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan (al-taqdir al-ittifaqi). Kedua, penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya. Dan, ketiga, penghitungan ganti rugi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (al-taqdir al-syar 'i). Hitungan dan perkiraan ganti rugi tersebut berasaskan pada beberapa hal. 1. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan taharru' terhadapnya. Namun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian—dengan catatan jika hal itu memungkinkan. 2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan darar secara langsung. Adapun darar tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan muta'addi tidak dapat dikenakan ganti rugi. 3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat darar yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan "aklu amwalinnas bi al-bathil (makan harta orang lain secara batil). Kecuali dalam kasus di mana tingkat ta'addi-nya sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera. 56 Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam Bila dilihat dari berat ringannya ganti rugi, para fuqaha' membaginya menjadi dua macam. Pertama, kerugian ringan (jawabir mukhaf-fafah) yang diukur berdasarkan tingkat kerugian (darar) yang diderita pihak korban. Kedua, kerugian berat (Jawabir mughallazah). Jawabir mukhaf-fafah terlihat pada kasus-kasus dalam kategori khatha'. Sedangkan jawabir mugallazah terlihat pada kasus-kasus syibhu al- `amad (perbuatan semi sengaja). Pelipatgandaan ganti rugi dikenakan kepada mereka yang mengambil harta orang lain dan membelanjakannya untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan dari tagliz (pemberatan dengan pelipatgandaan kerugian) adalah zijru al-muta'addi (membuat pelaku agar menjadi jera) tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Kendati demikian perbedaan antara al- `uqubah dengan daman selalu ada, setidaknya dapat diamati sebagai berikut: 1. Al-qatl syibhu al- 'amad (pembunuhan semi sengaja). Sisi tagliz dalam kasus pembunuhan ini adalah tingginya umur unta yang dijadikan sebagai diyat wajib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah Ibn Amr bahwa Rasulullah bersabda21: (bahwa dalam kasus pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cemeti dan tongkat, dendanya seratus unta, 40 di antaranya sedang mengandung). Hadis yang searti dengan itu juga diriwayatkan oleh Amr Ibn Syu'aib bahwa seseorang yang bernama Qatadah melempar anaknya dengan pedang sampai tewas. Karena itu, diyat yang dibebankan kepadanya adalah 30 ekor unta kategori hiqqah (umur 3 tahun masuk tahun ke 4), 30 unta lagi kategori jiz 'ah (umur 4 tahun masuk tahun ke 5), dan 30 ekor lagi kategori khilfah (unta yang sedang mengandung). 2. Mengambil harta orang lain yang sulit diletakkan pada wadah tertentu atau dijaga sepanjang waktu. Diriwayatkan dari Amr Ibn Syu'aib dari ayah dan neneknya berkata: "Rasulullah pernah ditanya tentang buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya. 3. Dengan demikian jawabir mugallazah tidak hanya pada luka-luka fisik, melainkan juga pada kerugian harta dalam situsi-situasi yang memerlukan "pemberatan terdakwa" seperi ingin memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain. Fenomena ini sekaligus memberikan keleluasaan hakim dalam menghitung dan memperkirakan kualitas dan kuantitas ganti rugi. F. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi Penggunaan istilah al-jabr oleh para fuqaha' dalam konteks daman yang dihubungkan dengan darar masih mengandung ambiguitas. Karena makna darar sangat beragam mengikuti konteksnya. Misalnya, al-jibr al-kamil (ganti rugi penuh) bertujuan untuk menetapkan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku (al-mutadarrir). Darar dalam konteks ini mencakup darar maliyah, darar badaniyah, dan darar adabiyah. Standarisasi jibru al-kamil bersifat kondisional, tergantung pengadilan dan usaha cerdas hakim. Karena betapa sulitnya mengukur rasa sakit yang bersifat psikis dibandingkan kerugian lain yang bersifat material. Dengan kata lain, rasa keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan sangat ditentukan oleh sikap, kecermatan, dan keadilan hakim itu sendiri. 21 Hadis dan takhrij-nya dapat dilihat dalam Nail al-Authar oleh al-Syaukani, hal. 7/167. 57 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Dalam menetapkan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip. Pertama, prinsip al-yusr (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosudur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya. Kedua, konsisten. Artinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula. Ketiga, menyamakan (al-musawat) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada pembedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan darar bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial. Dan keempat, hams terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti mgi yang akan dibebankan kepada mereka. 1. Prinsip al-Misli dalam Menetapkan Ganti rugi Prinsip persamaan (mabda' al-misliyah) dalam ganti mgi ditetapkan berdasarkan nas syariah antara lain firman Allah wajazau saiatin saiatun misluha. Disebut dengan istilah al-uqubah atau al-jaza' semata-mata dalam konteks almusyakalah/al-mumasalah (persamaan), dan juga untuk mengingatkan si pelaku agar menjadi jera. Prinsip al-mumasalah juga diperkuat oleh ayat fa mani'tada „alaikum fa'tadu `alahi hi misli ma i'tada `alaikum. Untuk membantu kita dalam menafsirkan ayat ini, perlu kiranya mengutip perkataan al-Zaila'i, seorang fuqaha' Hanafi, wa daman al-udawan masyruthun bi al-mumasalah bi al-nassi wa alijma'. Wasummiya daman al-muqabil i'tidaan hi thariq al-muqabalah li fi'li ali'tida' awu al-idhrar majazan la haqiqatan, li anna al-majazat awu daman la yakun saiyiah wala ta'ddiyan.22 Intl dari pernyataan al-Zaila'i bahwa ganti rugi pelanggaran disyaratkan hams sama berdasarkan nas dan ijma', sedangkan penamaan daman berdasarkan pelanggaran dalam konteks majazi, bukan pada makna hakikinya, karena ganti mgi menurut makna majazinya bukanlah sesuatu yang buruk atau merupakan suatu pelanggaran. Menghitung ganti mgi mengacu pada kaidah kesepadanan (al-misli) dengan mempertimbangkan metode syari' dalam menetapkan al-misli, al-qimah dan ujratu al-misli terhadap ganti mgi al-mal. Namun, manakala kaidah al-misli sulit diterapkan dalam kasus-kasus luka fisik (al-isabat al-badaniyah), karena luka fisik, sesungguhnya, tidak mungkin sepadan dengan ganti mgi dalam bentuk uang, maka syari' menetapkan ukuran-ukuran tertentu yang dapat direalisasikan yaitu aljawabir al-muqaddarah misalnya diyat (denda pembunuhan), al-urusy (denda luka), al-aqilah (denda pembunuhan kolektif), dan lain-lain. Hal ini kemudian oleh para fuqaha' disebut al-mumasalah al-hukmiyah. 22 58 Usman Ibn All al-Zaila'i, Tabyin al-haqoiq Syarh Kanzu al-Daqaiq, Kairo: Dar alKitab alIslami, Cet. II, 1990, hal. V: 223. Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam 2. Pencemaran Nama Baik (iza' al-muslim fi sum'atilu) Untuk melindungi kehormatan seseorang, syariah memulai dari masalah yang sederhana. Misalnya, larangan menuduh seseorang melakukan zina (al-qazf), larangan saling mencela dan memberi julukan jelek (al-tanabuz bi al-alqaf) atau menafikan ketumnan (nafyu al-nasab). Hal ini sesuai surat al-Hujarat ayat 11-12. Demikian pula dalam Surat al-Nur ayat 4-5. Sedang di dalam hadis disebutkan, almuslim man salimal muslimun min lisanihi wayadih (seseorang bam dikatakan muslim apabila menyelamatkan umat Islam dari gangguan ucapan dan prilakunya). Para fuqaha' kemudian merumuskan masalah pencemaran nama baik dalam bingkai al-maqasid al-khamsah li al-syariah (lima kemaslahatan) , yaitu menjaga agama, jiwa, moral, akal, dan harta. Hanya saja, para fuqaha' lebih banyak fokus pada hal-hal yang terkait dengan al- `ardh dalam pengertian yang sangat sempit dengan menjelaskan hukuman pelaku zina, hukuman bagi penuduh berbuat zina. Tegasnya, para fuqaha' lebih asyik menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan zina (al-qazj), atau hukum lain yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Al-Qur'an mengharamkan apa pun bentuk perbuatan yang menyentuh kehormatan muslim. Dalam surat al-Nur ayat 4 dan 5, al-Qur'an mengharamkan qazf, zina, dan hukumannya. Sementara dalam ayat 11 dan 12 Surat al-Hujarat mengisyaratkan berbagai bentuk pelanggaran yang menyentuh kehormatan dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya sukhriyah (pengejekan), al-lamz (mencela dan mengkritik dengan bahasa yang tidak etis), tanabuz bi al-qaaf (saling mencela dengan memberi julukan jelek), tajassus (memata-matai) dan al-gibah (umpatan). Betapapun terbatasnya konsep perlindungan nama baik yang telah dirumuskan para fuqaha', namun dapat diidentifikasi menjadi pelanggaran (alta 'addiyat) terhadap nama baik seseorang yang meliputi tuduhan melakukan zina dan tuduhan terhadap selain zina yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik. Oleh karena itu fungsi faqih termasuk hakim dalam hal ini adalah melakukan istimbath hukum sekaligus mengembangkan konsep perlindungan terhadap kehormatan. Tegasnya, mereka hams mewujudkan konsep tersebut berdasarkan keumuman konsep syariah dan maqasid-nya. 3. Hal-hal yang Menafikan Daman Pada prinsipnya daman diberlakukan kepada siapapun yang menyebabkan kerugian pihak lain. Namun demikian, daman juga tidak dapat diberlakukan kalau terdapat halangan (al-mawani') atau alasan pembenar, antara lain: a) Pemusnahan barang secara legal. Misalnya, khamar atau barang-barang sejenis tidak dapat diberlakukan ganti mgi terhadap muslim baik pribadi mapun kolektif. Karena khamar dan babi adalah harta yang pemanfaatannya dilarang oleh syariah (mal gairu mutaqawwim). Memusnahkan harta jenis ini termasuk suatu kewajiban syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanya saja ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan khamar dan babi yang dimiliki kaum zimmi juga hams dimusnahkan. 59 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 b) c) d) e) 23 60 ISSN : 2303-3274 Pemusnahan terhadap harta benda yang dilakukan oleh seseorang sematamata karena melaksanakan tugas (perintah dalam konteks ketaatan) seperti para pembantu hakim, tidak dibebani ganti rugi. Berbeda, misalnya perintah itu dalam konteks maksiat, maka ganti rugi menjadi suatu kewajiban. Apabila sesuatu yang diperintah tergolong boleh dilakukan (ja'iz al-fi‟l) serta dikerjakan atas dasar ketaatan terhadap perintah—ketaatan seorang pegawai terhadap atasan, misalnya—maka dalam hal ini perbuatan orang yang diperintah sama dengan perbuatan orang yang memberi perintah. Dengan demikian ganti rugi dibebankan kepada yang memberi perintah, dengan catatan jika perbuatan tersebut memang benar-benar mengharuskan ganti rugi. Melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dalam keadaan darurat. Misalnya melakukan perusakan terhadap harta benda orang lain, dalam keadaan terancam baik jiwa maupun hartanya oleh orang lain atau hewan, tidak dibebankan ganti rugi. Tentu saja terikat dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya mencegah terjadinya suatu kerugian dengan melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain hams bersifat tiba-tiba dan seketika. Tanpa direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat (halat al-darurah). Apabila seseorang dalam keadaan lapar atau haus yang dapat mengakibatkan kematiannya. Untuk mencegah kematian tersebut diperbolehkan makan atau minum milik orang lain, dengan syarat tidak melebihi kebutuhan. Dalam keadaan seperti ini kewajiban ganti mgi menjadi gugur, tetapi is diwajibkan untuk membayar makanan dan minuman itu. Pendapat tersebut disepakati oleh mazhab empat dan juga pendapat mazhab Zaidiyah. Ada kerelaan dari pihak yang dimgikan. Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membuang bajunya ke laut, atau merusak rumahnya, ternyata perintah itu dilakukan, maka orang tersebut tidak dibebani ganti mgi. Sebab, perintah untuk melakukan hal tersebut, masih dalam batas wewenangnya. Lagipula, yang melakukan perintah tersebut tidak termasuk pelaku pelanggaran (muta'addi). Apabila pembebanan ganti mgi itu tidak berguna (`adamu al-faidah fi altadhmin). Jika kaum muslim memusnahkan harta benda kaum pemberontak (al-bugat), atau sebaliknya al-bugat memusnahkan harta benda kaum muslim, masing-masing tidak dapat dibebani ganti rugi. Sebab, pembebanan ganti rugi kepada mereka tidak berguna. Umat Islam tidak boleh menanggung ganti rugi terhadap harta benda orang-orang bugat. Sebaliknya orang muslim pun tidak dapat memberlakukan ganti rugi terhadap kaum bugat mengingat tidak ada kewenangan pemerintah muslim terhadap mereka.23 Jami' al-Fushulain, hal. 2/78, Ibn Abidin, Raddu al-Mukhtar ala al-Durri al-Mukhtar, Beirut: Dar al-Kutub Cet. I, 1415H/1994M, hal. 5/140, Muhammad Ibn Ahmad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet.I, 1417 H/1996 M, hal.4/240. Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam G. Perubahan Status Yadu24 Amanah25 Menjadi Yadu Damanah Tidak terdapat perbedaan antara para fuqaha' bahwa yad al-wadi' (orang yang menerima titipan), al-musta jir (penyewa), al-mudarib (pelaku usaha), alsyarik (mitra usaha), al-rasul (utusan), al-ajir al-khas, wakil sukarela, wall, wasi, almultaqith atau orang yang menemukan dan memungut barang yang bertujuan untuk memperkenalkan barang adalah yadu amanah. Mereka tidak dibebani ganti rugi jika terjadi kerusakan barang pada saat berada dalam penguasaan mereka, kecuali kalau melakukan pelanggaran dan kecerobohan (ta'addi dan tafrith). Karena tangan-tangan ini secara keseluruhan tergolong penolong (al-irfaq wa alma 24 25 Al-yad menuru bahasa adalah salah satu anggota badan yang disebut tangan. Dalam pengertian majazi dapat bermakna nikmat, penguasaan terhadap sesuatu barang, kepemilikan atau juga dapat bermakna kekuatan. Menurut al-Zarkasyi, al-yad ada dua macam, yakni yad hissiyah yaitu tangan dalam pengertian konkret dan yad ma 'nawiyah yaitu tangan dalam pengertian abstrak. Yad hissiyah adalah mulai dari jarijari sampai dengan siku. Adapun yadma'nawiyah maksudnya penguasaan terhadap suatu barang baik karena kepemilikan maupun karena lainnya, karena dengan al-yad atau penguasaan terhadap suatu barang dapat ditasarrufkan (ditukar, dijual dan lainlain). Lihat Badruddin al-Zarkasyi, al-Mantsur fi al-Qawa 'id, Dar al-Kuwait, Cet. II, 1405 H, hal 3/370. Para fuqaha' kemudian membagi al-yad al-ma 'nawiyah menjadi yad daman dan yad amanah. Yad daman adalah yad yang menguasai barang (al-haiz li al-syai‟) tanpa seizin pemiliknya. Penguasaan dengan cara merampas, mencuri atau dengan cara lain yang tergolong 'udwan. Atau menguasai barang dengan seizin pemiliknya akan tetapi dengan maksud memilikinya seperi mengambil barang dengan menuntut agar pemilik menjual barang tersebut kepadanya, dan pemungut barang (almultaqith) dengan niat untuk memiliki Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, yad al-musta 'ir (peminjam) adalah yad daman. Pendapat ini disepakati oleh mazhab Malikiyah pada jenis barang yang dapat disembunyikan seperti perhiasan dan pakaian. Mazhab Hanafiyah juga berpendapat bahwa yad al-murtahin (penerima gadai) adalah yad daman. Demikian pula pendapat mazhab Maliki terutama pada barang-barang yang dapat disembunyikan. Lihat Ali Ibn Muhammad al-Mawardi al-Hawi alKabir Syarh Mukhtasar al-Muzani, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1414 H/1994 M, hal. 8/191, 9/254, 255; Ahmad Ibn Idris al-Qurafi, al-Furuq fi Anwar al-Buruq fi Anwai alFuruq, Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Beirut: Dar al-Kutub al'ilmiyah, Cet. I, 1418 H/ 1998 M, hal.2/207; Zarkasyi, al-Qawa 'id, hal 2/323,332, 339; Abdurrahman Ibn Syihabuddin Ibn Rajab, al-Qawa 'id al-Fiqhiyah, Kairo, 1392 H./ 1997 M, hal 60; Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Beirut: Dar Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1415H/1994M, hal. 2/267; dan Ibn Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid, Beirut: Dar al-Kutub Cet. I, 1418 H/1997 M, hal. 2/263. Amanah dalam istilah fiqh adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda berdasarkan suatu akad atau bukan akad, baik akad itu tergolong akad is tihfaz (akad pemeliharaan barang) seperti wadi 'ah , maupun akad is ti jar (akad untuk penggunaan jasa barang) seperti Sarah. Amanah yang tanpa menggunakan akad seperti luqathoh (barang pungutan) yang berda pada al-multaqith selama dalam penyiarannya. Sedangkan di dalam Majallatu al-Ahkan al'Adliyah menyebutkan bahwa amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang berupa akad, seperti harta benda yang disewakan atau yang dipinjamkan, maupun harta yang berada di tangan orang lain tanpa melalui akad atau tanpa kesengajaan. Sedangkan al-amin adalah orang-orang yang sedang mengemban amanah. Lihat Muhammad Ruwas Qol'aji dan Hamid Sodiq Qunaibi, Mu jam Lugat al-Fuqaha' "Arabi-Inklizi, Beirut: Dar'al-Nafa'is,Ceti',1408H/1988M. 61 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 'unah).26 Jika tangan-tangan mereka dibebani ganti rugi, maka kepentingan publik akan terabaikan. Akan tetapi fuqaha' berbeda pendapat pada sebagian al-yad yang lain seperti yad al-mustajr (peminjam barang), yad al-murtahin (penerima gadai), yad alwakil dengan upah, yad ajir al-musytarak, dan yad sunna' (pembuat barang pada akad istisna'). Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa tangan-tangan mereka termasuk tangan amanah sehingga kalau terjadi kerusakan barang tidak dibebani ganti rugi. Sedangkan fuqaha' yang lain berpendapat bahwa tangan-tangan mereka adalah yadu daman, artinya jika terjadi kerusakan pada barang pada saat dalam mpenguasaan mereka dibebani ganti rugi.27 Perbedaan pendapat tersebut muncul karena beberapa sebab. Pertama: Sebagian al-aidi (jamak dari al-yad) tersebut dari satu sisi memiliki kemiripan secara dominan dengan al-aidi al-aminah, sedang di sisi lain kemiripannya juga dominan dengan al-aidi al-daminah. Fuqaha yang mentarjih kemiripannya dengan al-aidi al-aminah menjadikannya bagian dari yad amanah sendiri, sebaliknya fuqaha' yang mentarjih kemiripannya dengan al-aidi al-daminah menjadikannya bagian dari al-yad al-daminah.28 Kedua sebagian fuqaha' melakukan istihsan untuk menetapkan ganti rugi terhadap al-aidi al-aminah untuk mengantisipasi kerugian akibat kerusakan barang karena suatu kecerobohan dan kelalaian mereka. Ketiga terdapat perbedaan pendapat tentang subut-nya sejumlah nas yang berkaitan dengan alaidi. Terlepas dari silang pendapat tersebut status yadu amanah dapat berubah menjadi yadu damanah karena antara lain pertimbagan „urf atau tradisi kolektif yang berlaku di tengah masyarakat. Pendapat ini umum di kalangan fuqaha' Hanafiyah dan Malikiyah. Contoh konkret mengenai masalah tersebut dapat ditemukan dalam filth mazhab Hanbali yang mengatakan bahwa para hurras (tukang jaga, satpam untuk masa sekarang) barang tidak dapat dibebankan ganti rugi. Sebab mereka tergolong yadu amanah. Namun demikian, seperti dikemukakan oleh penulis Kasyfu alQina',29 para hurras tersebut sewaktu-waktu dapat dibebani ganti rugi berdasarkan pertimbangan Jadi, menurut Ibn Nujaim, para pekerja dan peminjam barang dikenakan ganti rugi jika terjadi kerusakan akibat kecerobohan atau kelalaian. Selain faktor 'toy; unsur ta addi (perlakuan yang melampaui wewenang baik secara syara' maupun 'yid) juga dapat menyebabkan ganti rugi bagi yad amanah. Hal ini menjadi kesepakatan para fuqaha' seperti ta 'addi yang dilakukan oleh alwadi' (yang diberi kepercayaan memegang titipan) terhadap al-wadi'ah (titipan) 26 27 28 29 62 Al-Mawardi, al-Hawi, hal. 8/192, 394, 9/104, 10/385. Lihat referensi sejumlah fiqh klasik dalam Nazih Hammad, Qodoya Fiqhiyah Mu 'asirah fi almal wa al-Iqtisad, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. I, 1421 H/ 2001 M, hal. 370 Lihat al-Muqaddimat al-mumahhidat, hal. 2/246, 368, al-Mawardi, al-Hawi, ha. 8/191, 9/254, al-Qurafi, al-Furuq, hal. 2/207, Ibn Rajab, al-Qawa 'id, hal. 60, Kasyfu al-Qina', hal. 92, alZakhirah, hal. 8/112. Al-Buhuti, Kasy-syaf al-qincz ', Makkah: Mathba'ah al-Hukumah 1394 H, hal. 2/69. Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam dengan merusak atau memanfaatkan tanpa seizin pemiliknya. Atau juga ta 'addi yang dilakukan oleh mudharib (yang melakukan usaha dalam akad mudarabah) ketika mengerjakan sesuatu di luar kontrak dengan sahib al-mal (pemilik modal). Seperti juga al-ta addi yang dilakukan oleh al-ajir (tenaga sewaan/orang upahan) dengan tidak mengindahkan perintah al-musta jir (orang yang menyewa tenaga), atau juga tindakan wakil (wakil) yang melampaui wewenang yang didelegasikan oleh al-muwakkil (pihak yang diwakili). Mereka ini terkena kewajiban daman karena sebagai pelaku langsung (mubasyir) yang mengakibatkan kerusakan, atau penyebab rusaknya barang secara zalim dan adanya unsur permusuhan. Jika terjadi perselisihan antara al-amin dengan sahib al-mal tentang prilaku ta 'addi ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada ahli atau orang yang memiliki kompetensi untuk itu. Solusi seperti ini sesuai dengan petunjuk Majallatu alAhkam al-Syar 'iyah `ala Mazhabi Ahmad.30 Al-tafrith menurut bahasa al-taqshir dan al-tadhyi' (kelalain, kealpaan, kesembronoan). Sedangkan al-Ifrath bermakna al-israf wa mujawazatu al-had (melampaui batas, pemborosan). Menurut al-Jurjani31 al-ifrath digunakan pada kesewenangan yang berlebihan melampaui porsi yang normal (tajawazu al-had min janib al-ziyadah wa al-kamal). Sedangkan al-tafrith digunakan pada sikap minimalis yang tidak proporsional (tajawazu al-had min jihat al-nuqshon wa altaqshir). Para fuqaha' sepakat bahwa yadu amanah dapat berubah status menjadi yadu damanah karena perilaku tafrith. Hal ini bisa terjadi pada mudharib, wadi', dan musta jir. Standar tafrith yang mengharuskan daman itu ditakar dengan al- urf. Sedangkan tatawwu 'ul amin bi iltizam ad-daman ba 'da al- `aqdi (kesanggupan dan kerelaan dari al-amin secara suka rela untuk melakukan ganti rugi setelah akad), menurut mazhab Maliki termasuk dalam kategori tabarru'. Selain itu, pertimbangan maslahah juga dapat memposisikan yadu amanah menjadi yadu damanah. Tentunya kemaslahatan pihak yang dikorbankan. Terakhir adalah al-tuhmah. Maksudnya, terdapat dugaan kuat bahwa terjadi kebohongan dari al-amin yang menyatakan bahwa kerusakan barang bukan karena kelalaian atau kecerobohannya, melainkan faktor lain di luar kemampuannya. Klaim seperti ini sangat mungkin dilakukan oleh mereka yang berstatus yadu amanah yang tidak menyadari tanggung jawabnya. Atas dasar ini ganti rugi tetap diberlakukan kepada mereka. Demikian pula yadu amanah berubah menjadi yadu damanah karena syaratsyarat yang ditetapkan secara sepihak (isytirath daman `ala al-amin), namun mendapat persetujuan dari pihak yadu amanah baik itu mudharib, musta jir, wadi', wakil, syarik atau lainnya. Tetang masalah ini terdapat silang pendapat di antara para fuqaha'. Pendapat pertama, syarat yang ditetapkan tersebut adalah batal karena tidak sejalan dengan karakteristik akad yang berstatus amanah. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan fuqaha' Hanabilah 30 31 Al-Qori, Majallatu al-Ahkam al- Adliyah Mazhabi Ahmad, Jedah: Tihamah, 1401 H. Syarif al-Jurjani, al-Ta 'rifat, al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1971, hal. 43. 63 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 dalam salah satu pendapat mereka yang populer. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh al-Sauri, Auza'i, Ishaq, Nakha'i, dan Ibn alMunzir. Pendapat kedua, menetapkan syarat karena faktor yang mengkhawatirkan pemilik modal misalnya, dapat dibenarkan dan diberlakukan jika sesuatu yang dikhawatirkan itu dalam kenyataannya merusak barang sehingga mengakibatkan kerugian pada pemilik modal. Pendapat ini dikemukakan oleh Mutharrif dari mazhab Maliki. Pendapat ketiga, syarat tersebut sahih dan mengikat. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Usman al-Buttiy, Ubaidillah ibn Hasan al-`Anbari, Dawud al-Zahiri dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Walaupun pendapat ini kurang populer di kalangan fuqaha' Malikiyah, dan pendapat yang tergolong lemah dalam mazhab Hanafi, namun pendapat ini mendapat dukungan dari Imam Syaukani. Penutup Ide daman dalam hukum Islam bersamaan dengan datangnya sumber hukum Islam sendiri. Sejumlah ayat dan hadis secara eksplisit telah mengisyaratkan daman ini. Lalu kemudian dikembangkan oleh para fuqaha' dalam kontek perdata dan pidana. Dalam konteks perdata para fuqaha, khususnya al-Qurofi dan al-qz Ibn Abdi Salam menggunakan istilah al-zawajir. Sedangkan dalam kontek pidana mereka menggunakan istilah al-zawajir. Adapun istilah al-masuliyah barn banyak ditemukan dalam fiqh-fiqh karya ahli hukum Islam modem. Secara garis besar daman muncul karena darar badaniyah, darar maliyah dan darar sangat mungkin terjadi di luar fisik dan harta, seperti pencemaran nama baik. Tetapi terdapat darar yang kualifikasinya tidak mudah dinominalkan dengan ganti rugi dalam bentuk uang misalnya. Karena itu berapa jumlah ganti rugi yang hams dibayarkan selain yang tidak ditetapkan berdasarkan nas. Persoalan ini kembali kepada al- `urf yang berlaku di masyarakat. Karena itu besarnya ganti rugi dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika cara ini sulit dilakukan maka besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan ketetapan dari pembuat undangundang. Namun demikian seorang hakim punya wewenang untuk menetapkan nominal ganti rugi asal sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. DAFTAR PUSTAKA Al-Quran al-Karim Ahmad Siraj, Muhammad, Daman al- `Udwan fi al-Fiqh al-Islami (Dirdsah Fiqhiyah Muqdranah bi ahkeim al-masuliyah al-Taqshiriyah fi al-qanun), al-Muassasah al-Jami'iyyah li al-Dirdsat wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. Atasi, Syarah Majallatu al-Ahkam al- Adliyah, dicetak di Hims Suriah, 1352 H. AlBagdadi, Majma' al-Damanat, Mesir: al-Khairiyah, 1388 H. Al-Buhuti, Kasy-syaf al-qina ', Makkah: Mathba'ah al-Hukumah 1394 H. 64 Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam Al-Dabbo, Ibrahim Fadil, Daman al-Manafi' dirasah muqaranah fi al-fiqh alislami wa al-qanun al-madani, Amman, Beirut: Dar al-Bayariq, Dar `Ammar, Cet. I, 1417 H/1997. Al-Dasuqi, Muhammad Ibn Ahmad, Hasyiyah `ala al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet.I, 1417 H/1996 M. Al-Hamawy, Ahmad Ibn Muhammad, Gamzu al-Basha'ir wa Syarah al- Asybelh wa Bairut: Dar al-Kutub Cet. 1405 H/1985 M. Ibn Abidin, Raddu al-Mukhtar ala al-Durri al-Mukhtar, Beirut: Dar al-Kutub al`ilmiyah, Cet. I, 1415H/1994M. Ibn Hajar al-Asqalani, al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadis al-Rafi al-Kabir, Mesir: Syarikat al-Thiba'ah al-Fanniyah, 1384 H. Ibn Rajab, Syihabuddin, al-Qawa 'id al-Fiqhiyah, Kairo, 1392 H/ 1997 M Ibn Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1418 H/1997 M. Al-Jurjani, Syarif, al-Ta 'rifat, al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1971. Majduddin alFairuzabadi, al-Qamus al-Muhit, Kairo: Dar al-Hadis, tt. Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad, al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzani, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1414 H/1994 M Qol'aji, Muhammad Ruwas dan Qunaibi, Hamid Sodiq, Mu jam Lugat alFuqaha— Arabi-Inklizi, Beirut: Dar'al-Nafa'is, Cet.II, 1408 H/1988 M. Al-Fatlawi, Shahib `Ubaid, Daman al- `uyub watakhallafa al-muwasafat fi `Uqud al-Bai', Amman: Maktabah Dar al-Saqofah li al-Nasyr wa al-tauzi', Cet. I, 1417 H/1997 M. Al-Qori, Majallatu al-Ahkam al- Adliyah `ala Mazhabi Ahmad, Jedah: Tihamah, 1401 H. Al-Qurafi, Ahmad Ibn Idris, al-Furuq fi Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq, Mansyurat Muhammad Ali Baidhun, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Cet. I, 1418 H/ 1998 M. Al-Sarakhsi, al-Mabsut, Mesir: al-Sa'adah, 1324 H. Suyuthi, Jalaluddin, al-Asybah wa al-Naza 'ir, Beirut: Muassasah al-Kutub alSaqofiyah, Cet. 1, 1415 H/1994 M. Al-Syarbini, Muhammad Ibn Ahmad, Mugni al-Muhtaj, Beirut: Dar Kutub al„ilmiyah, Cet. I, 1415H/1994M. Al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar, Mesir: Mustafa al-Babi alHalabi, 1380 H. Al-Zaila'i, Usman Ibn Ali, Tabyin al-haqoiq Syarh Kanzu al-Daqaiq, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, Cet. II, 1990. Al-Zarkasyi, Badruddin, al-Mantsur fi al-Qawa'id, Dar al-Kuwait, Cet. II, 1405 H. Al-Zarqa', Mustofa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqhi al-Am (al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid),Beirut: Dar al-Fikr, hal. 1032. Al-Zuhaily, Wahbah, al-Mas 'uliyah 'an Fi'li al-Gain, Damaskus: Dar alMuktabi, Cet. 1, 1416 H/1995 M. 65 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 66 ISSN : 2303-3274 HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia) Dina Sunyowati Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga e-mail :[email protected] Abstrak Kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (pacta sunt servanda). Perjanjian internasional yang telah disepakati dan di sahkan dalam suatu ratifikasi oleh suatu negara, maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua dan menjadi sumber hukum bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan. Hal ini berlaku juga di Indonesia. Setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang sudah tertuang dalam suatu persyaratan ratifikasi atau tidak, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sumber Hukum, Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional Abstract Countries agreement contained in an international agreement in the form of bilateral agreements, regional and multilateral agreements that are binding on the parties and a law for that entered into an agreement (pacta sunt servanda). International agreements that have been agreed and validated in a ratification by a country, then the agreement is valid and binding upon all be a source of law for the enforcement of law in making decisions. This is true also in Indonesia. Any international agreement that has been followed by Indonesia, which is contained in a ratification requirement or not, still have the force of binding for both parties. Keywords : International Law, Sources of Law, International Treaties, International Agreements. 1. Pendahuluan Pembahasan mengenai sumber hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam bidang hukum, bukan hanya dalam tataran Hukum Nasional (HN) tapi juga Hukum Internasional (HI). Pemahaman tentang ini mutlak diperlukan dikarenakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, sumber hukum menjadi tempat diketemukannya dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman. Dewasa ini terdapat kecenderungan membicarakan kembali mengenai sumber hukum dalam hukum internasional, karena perkembangan masyarakat intemasional Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 yang sangat cepat dan hukum internasional itu sendiri.Sumber hukum intemasional berbeda dengan Hukum Nasional. HI memiliki keunikan tersendiri, terutama ketiadaan pernyataan yang secara eksplisit menyebutkan apa sumber-sumber hukum intemasional itu sendiri yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan sengketa internasional. HI tidak memiliki organ-organ yang pada umumnya ada di tingkat nasional, seperti lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. (Martin Dixon, 1993, 2003, 19). Dalam Statuta the International Court of justice (ICJ), salah satu main organ PBB yang berfungsi mengadili sengketa internasional antar negara, disebutkan tentang sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan tuntunan bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang masuk ke International Court of justice atau Mahkamah Intemasional, Dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta ICJ menyebutkan bahwa : "The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law; c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the provisions of Article 59, [.e. that only the parties bound by the decision in any particular case] judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law." Sedangkan dalam ayat (2)nya, memberikan kekuasaan bagi ICJ untuk memutuskan kasus secara pantas dan adil (ex aequo et bono) berdasarkan prinsipprinsip umum ("This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto”).Mahkamah Internasional mempunyai kekuasaan untuk memutus berdasarkan pada pertimbangan hakim atau arbitrator sebagai „the fairest solution in the circumstances' tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku. (Hugh Thirlway, dalam Jawahir Thontowi, 2003, 121) Urut-urutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) di atas bukanlah menunjukkan urutan atas yang paling penting dan utama, melainkan hanyalah untuk memudahkan saja.Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dari empat sumber tersebut, dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu sumber hukum utama (primer / urutan a, b dan c) dan sumber hukum tambahan (subsidier / urutan d). Persoalan mana sumber hukum yang terpenting/paling utama tergantung dari mana sudut pandang Hakim dalam memutus sengketa. (Mochtar Kusumaatmadja, 1989, 34). Statuta MI meletakkan traktat/perjanjian pada urutan atas, disebabkan karenaadanya protes dari negara-negara yang barn merdeka, apabila hukum internasional bersumber pada kebiasaan internasional yang dipandang bersifat Eropa centris, hukum internasional modern (diatas tahun 1945) lebih banyak mengatur masalah sosial ekonomi dan hal ini tidak akan ditemukan dalam kebiasaan internasional. Perjanjian internasional memberi kepastian hukum, karena 68 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional tertulis dan hukum internasional modern lebih bersifat mencegah konflik antar negara, daripada menyelesaikan konflik. Sementara itu dari sudut pandang historis / sejarah, yang paling utama adalah kebiasaan internasional, karena merupakan sumber hukum yang tertua. Sedangkan dari sudut pandang perkembangan hukum internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang paling berperan, karena memberi keleluasaan kepada MI untuk menemukan atau membentuk kaidah hukum baru. Hugh Thirlway membedakan antara aturan-aturan utama (primary rules) dan aturan-aturan sekunder (secondary rules) . Meskipun pembedaan ini berasal dari pembedaan yang ada dalam sistem hukum nasional, namun pembedaan ini cukup menolong untuk memahami sifat-sifat dari sumber hukum internasional (Jawahir Thontowi, 2006, 54). Dlam setiap sistem hukum terdapat sekumpulan prinsipprinsip dan aturan-aturan yang menjabarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum dari sistem tersebut yang kemudian dikenal dengan aturan-aturan utama. Sedangkan setiap sistem juga memiliki aturan yang ditujukan untuk menerapkan apa yang termasuk aturan-aturan utama dan bagaimana aturan tersebut dapat terwujud, diterapkan dan dirubah, yang kemudian dikenal dengan aturanaturan sekunder.(Jawahir Thontowi, 2006,54) Keberadaan sumber hukum tersebut, menyebabkan negara-negara hams mengikuti dan mematuhi aturan-aturan utama, karena aturan ini tersedia dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat negara-negara yang mengikatkan dirinya pada perjanjian (treaty —law). Negara yang menjadi peserta dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat berdasarkan hukum perjanjian internasional hams tunduk pada kesepakatan /perjanjian tersebut, sebab negara terikat dengan pacta sund servanda. Memang tidak aturan yang menyatakan bahwa prinsip tersebut dikatakan sebagai prinsip yang tertinggi dalam hubungan antar negara yang terikat dengan perjanjian internasional,tetapi seperti dinyatakan dalam Pasal 38 Ayat (1) bahwa dalam memutuskan suatu sengketa, maka hams mendasarkan pada hukum internasional, yakni menerapkan treaty dan kebiasaan internasional yang ada, dan hal ini merupakan pengakuan terhadap traktat sebagai sumber hukum formal, sedangkan Statuta merupakan sumber material dan aturan-aturan sekunder dari treaty make-law. 2. Perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Pelanggaran terhadap hukum internasional akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan seining dengan perkembangan masyarakat internasional, dan menjadi pembahasan yang sangat menarik perhatian karena dalam kenyataan negaranegara sebagai subyek hukum internasional tunduk dan mentaati kaidah-kaidah hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa intemasional. Struktur masyarakat internasional yang koordinatif, antara lain ditandai oleh tiadanya badan supra nasional di atas subyek-subyek atau anggota masyarakat intemasional yang sama derajad antara satu dengan lainnya. Apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional? Sementara itu diketahui bahwa tiadanya badan supra nasional yang berwenang membentuk dan memaksakan berlakunya hukum intemasional, akan dapat menimbulkan sikap skeptis yaitu, apakah hukum 69 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 internasional itu memang benar-benar ada atau memenuhi kualifikasi sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, hukum hanya dipandang sebagai suatu mekanisme yang bekerja sesuai dengan norma-norma yang diwujudkan dengan adanya aparat-aparat penegak hukum serta sanksi sebagai upaya memaksakan dan mendayausahakan hukum itu sendiri.Padahal, sebenarnya hukum itu tidak saja sekedar mekanisme pelaksanaan dan pemaksaan norma-norma melainkan jauh lebih luas dari pada itu.Dalam tata masyarakat intemasional, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.Menurut Mochtar Kusumaatmadja, semua kelemahan kelembagaan (institusional) ini telah menyebabkan beberapa pemikir mulai dari Hobbes dan Spinoza hingga Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional, dan menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya. Para ahli menempatkan hukum intemasional segolongan dengan "the laws of honour" dan "the laws set by fashion" sebagai "rules o fpositive morality". (Mochtar Kusumaatmadja, 1989, 35) Lebih jauh Austin memandang hukum itu sebagai perintah yakni perintah dari penguasa kepada pihak yang dikuasai. Penguasa itu memiliki kedaulatan yang didalamnya termasuk pula kekuasaan untuk membuat hukum yang akan diberlakukan kepada pihak yang berada di bawah kekuasaannya. Hal ini berarti bahwa, jika suatu peraturan tidak berasal dari penguasa yang berdaulat, peraturan semacam itu bukanlah merupakan hukum, melainkan hanyalah merupakan norma moral, seperti misalnya norma kesopanan dan norma kesusilaan. Pandangan Austin ini mendasarkan adanya hukum pada badan yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk memaksakan berlakunya hukum kepada pihak yang dikuasainya, juga merupakan penyangkalan atas eksistensi hukum yang berasal dari atau tumbuh dalam pergaulan hidup masyarakat, seperti misalnya hukum kebiasaan (customary law). Menurut Austin, hukum kebiasaan itu bukanlah hukum melainkan hanyalah norma moral saja. Jika pandangan Austin ini diterapkan pada hukum intemasional, dimana masyarakat internasional dan tata hukum intemasionaltidak mengenal badan supra nasional, dapat dikatakan bahwa Austin memandang hukum internasional itu bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanyalah merupakan norma moral intemasional saja. Bagi Austin, walaupun kini sudah ditinggalkan oleh para ahli hukum intemasional, tetapi tidak jarang masih menghinggapi pola pikiran para ahli hukum terhadap eksistensi hukum internasional itu sebagai suatu norma hukum. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena kita sudah terbiasa dalam suasana masyarakat dan hukum nasional yang seperti telah diuraikan di atas, secara puma memiliki alat-alat perlengkapan atau lembaga-lembaga dengan tugas dan wewenang yang jelas dan tegas sehingga dapat memaksakan berlakunya hukum nasional kepada subyek-subyek hukum nasional. Dalam tata masyarakat dan hukum nasional, peranan lembaga dan aparataparat penegak hukum beserta sanksi hukumnya tampak sangat menonjol dan 70 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional mendominasi mekanisme pembentukan, pelaksanaan dan pemaksaan hukum itu sendiri.Dalam kenyataan memang terdapat peraturan-peraturan hukum nasional yang seringkali mengalami kelumpuhan, disebabkan oleh karena kurang berperannya lembaga dan aparat penegak hukum tersebut. Apalagi kalau lembaga dan aparat penegak hukum itu tidak ada sama sekali, seperti halnya dalam masyarakat dan hukum internasional, sudah barang tentu akan mengakibatkan hukum nasional itu akan lumpuh sama sekali. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika timbul pandangan pada sebahagian ahli hukum, lebih-lebih di kalangan orang yang awam hukum bahwa adanya lembaga dan aparat-aparat penegak hukum serta sanksi hukum yang tegas, merupakan faktor yang esensial bagi adanya suatu kaidah hukum.Dengan demikian hukum dipandang selalu dalam keterkaitannya dengan lembaga dan aparat penegak hukum.Tanpa adanya lembaga dan aparat, maka hukum itupun dipandang seperti tidak pernah ada. Sebenamya pandangan seperti tersebut di atas, sudah lama ditinggalkan.Lembaga dan aparat penegak hukum serta sanksi hukum bukanlah merupakan unsur yang paling menentukan dari suatu norma hukum. Eksistensi suatu norma hukum sebenamya lebih ditentukan oleh sikap dan pandangan serta kesadaran hukum dari masyarakat. Kalau masyarakat merasakan, menerima dan mentaatinya sebagai suatu norma hukum, jadi sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, walaupun tidak ada lembaga yang membuat maupun aparat yang memaksakannya, maka norma demikian itu adalah merupakan norma hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perkembangan ilmu hukum kemudian telah membuktikan tidak benamya anggapan Austin tersebut mengenai hukum.Kita cukup mengingat adanya hukum adat di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang tersendiri untuk menginsyafi kelirunya pikiran Austin mengenai hakikat hukum. Keberadaan badan legislatif, badan kehakiman dan polisi merupakan ciri yang jelas dari suatu sistem hukum positif yang efektif, akan tetapi ini tidak berarti bahwa tanpa lembaga-lembaga ini tidak terdapat hukum. Keberadaan dan hakikat hukum internasional sebenamya tidak perlu diragukan lagi, sehingga memerlukan dasar kekuatan mengikat hukum internasional.Teori tentang kekuatan mengikat hukum internasional, seperti teori hukum alam (natural law) mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional sejak permulaan pertumbuhannya. Ajaran ini yang mula-mula mempunyai ciri keagamaan yang kuat, untuk pertama kalinya dilepaskan dari hubungannya dengan keagamaan oleh Hugo Grotius.Dalam bentuknya yang telah disekularisir maka hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.Menurut para penganut ajaran hukum alam ini, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain karena "hukum alam" yang ditetapkan pada kehidupan masyarakat bangsabangsa. Dengan demikian negara terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu "hukum alam". Pendapat ini kemudian dalam abad 71 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 XVIII lebih disempurnakan lagi, antara lain oleh seorang ahli hukum dan diplomat bangsa Swiss, Emmerich Vattel (1714-1767) dalam bukunya Droit des Gens. Teori-teori yang didasarkan pada asas hukum alam sangat samar dan tergantung dari pendapat subyektif mengenai "keadilan", kepentingan masyarakat internasional dan konsep lain yang serupa. Bahkan dalam hukum internasional, banyak pandangan yang subyektif tentang isi dan pengertian hukum alam, karena kaidah moral dan keadilan dimaknai beragam oleh para ahli yang mengemukakannya. Hal ini disadari karena taraf integrasi yang rendah dan masyarakat internasional dewasa ini dan adanya pola hidup kebudayaan dan sistem nilai yang berbeda dari satu bangsa ke bangsa lain, maka pengertian tentang nilainilai yang biasa diasosiasikan dengan hukum alam mungkin sekali juga akan berbeda, walaupun istilah yang digunakan mempunyai kesamaan. Walaupun demikian teori hukum alam dan konsep hukum alam telah memberi pengaruh besar dan baik terhadap perkembangan hukum internasional, karena telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional dan perkembangan selanjutnya. Aliran lain mengenai kekuatan mengikat hukum internasional adalah keinginan suatu negara untuk tunduk pada HI atas kehendak negara itu sendiri, "Selbst limitation theorie" atau Self limitation theory. Tokoh aliran ini adalah George Jellineck, yang meletakkan dasar bahwa negaralah yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu tunduk pada hukum internasionalatas kemauan sendiri.Aliran ini menyandarkan pada falsafah Hegel yang mempunyai pengaruh sangat kuat di Jerman.(Mochtar Kusumaatmadja, 1989, 44) . Hukum internasional bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Kelemahan dari teori-teori ini ialah bahwa mereka tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya hukum internasional yang tergantung dari kehendak negara dapat mengikat suatu negara. Muncul pertanyaan bagaimana jika suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk terikat pada hukum internasional, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi, masih patutkah dinamakan hukum? Teori ini tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru, sejak menjadi bagian dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh hukum internasional, terlepas dari mau atau tidak tunduk pada hukum internasional. Begitu juga mengenai hukum kebiasaan internasional belum terjawab dalam teori ini. Berbagai kelemahan dan keberatan dari aliran tersebut dicoba diatasi oleh aliran lain dari teori kehendak negara yang menyandarkan kekuatan mengikat hukum internasional pada kemauan bersama. Triepel berusaha membuktikan bahwa hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu per satu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional.Sementara itu aliran lain menyatakan bahwa kehendak bersama negara ini berlainan dengan kehendak negara yang spesifik yang tidak perlu dinyatakan, disebut sebagai "Vereinbarung".Vereinbarungstheorie ini mencoba menerangkan sifat mengikat hukum kebiasaan (customary law) dengan 72 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional mengatakan bahwa kehendak untuk terikat kepada hukum internasional diberikan secara diam-diam (implied),dengan melepaskannya dari kehendak individual negara dan mendasarkannya kepada kemauan bersama (Vereinbarung), Triepel mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara tetapi membantah kemungkinan suatu negara melepaskan dirinya dari ikatan itu dengan suatu tindakan sepihak. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara (teori voluntaris) ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai alam pikiran dunia ilmu hukum di benua Eropa-terutama Jerman pada bagian kedua abad ke -19. Selain teori kehendak diatas, muncullah madzab Wienna, yang pada hakikatnya ingin mengembalikan kekuatan mengikatnya hukum internasional itu pada kehendak (atau persetujuan) negara untuk diikat oleh hukum internasional dalam suatu hukum perjanjian antara negara-negara.Teori kehendak mempunyai kaitan dengan teori alami perjanjian. Persetujuan negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki adanya hukum atau norma sebagai suatu yang telah ada terlebih dahulu dan lepas dari kehendak negara (Aliran obyektivis). Bukan kehendak negara melainkan suatu norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Menurut madzab Wienna ini, kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan begitu seterusnya.Akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum dimana terdapat kaidah dasar (Grundnorm) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan hams diterima adanya sebagai suatu hipotese asal (Ursprungshypothese) yang tidak dapat diterangkan secara hukum. Kelsen merupakan tokoh dari madzab Wienna ini mengemukakan asas "pacta sunt servanda" sebagai kaidah dasar (Grundnorm) hukum internasional. (Mochtar Kusumaatmadj a, 1989, 48) Ajaran madzab Wienna ini mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar, dapat menerangkan secara logis dari mana kaidah hukum intemasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya, akan tetapi ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat. Dengan demikian, seluruh sistem yang logis tadi menjadi tidak mempunyai kekuatan, sebab tidak mungkin persoalan kekuatan mengikat hukum intemasional itu disandarkan atas suatu hipotese.Dengan pengakuan bahwa persoalan kekuatan Grundnorm merupakan suatu persoalan di luar hukum (metayuridis) yang tak dapat diterangkan, maka persoalan mengapa hukum internasional itu mengikat dikembalikan kepada nilai-nilai kehidupan manusia di luar hukum yakni rasa keadilan dan moral.Dengan demikian, teori mengenai dasar berlakunya atau kekuatan mengikat hukum internasional setelah mengalami perkembangan sekian lama, kembali lagi kepada teori yang tertua mengenai hal ini yakni teori hukum alam.Timbulnya kembali teori hukum alam dalam ilmu hukum pada umumnya setelah Perang Dunia II juga disebabkan karena kebutuhan orang untuk kembali mempunyai pegangan hidup dan nilai yang pasti, setelah menyaksikan 73 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 kemerosotan spiritual di masa tahun tiga dan empat puluhan. (Mochtar Kusumaatmadj a, 1989, 49) Aliran lain yang berusaha menerangkan kekuatan mengikat hukum internasional tidak dengan teori yang spekulatif dan abstrak melainkan menghubungkannya dengan kenyataan hidup manusia, yaitu madzab Perancis, dengan tokohnya antara lain Fauchile, Scelle dan Duguit yang mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional seperti juga segala hukum pada faktor biologis, sosiologis dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (fait social) yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya segala hukum, termasuk hukum internasional. Menurut tokoh tersebut, persoalannya dapat dikembalikan pada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, keinginan untuk bergabung dengan manusia lain dan kebutuhannya akan solidaritas. Kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai orang seorang menurut mereka juga dimiliki oleh bangsa-bangsa.Sehingga dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat. Keberadaan hukum internasional sebagai suatu norma hukum, sebagai hukum yang tumbuh, berlaku dan berkembang di dalam masyarakat internasional-tanpa dibuat dan dipaksakan oleh lembaga supra nasional- sangat sulit untuk dibantah eksistensi hukum internasional itu sebagai suatu norma hukum. Eksistensi hukum internasional sekarang ini tidak perlu diragukan lagi.masyarakat internasional kini telah menerimanya sebagai suatu norma hukum yang mengatur masyarakat internasional.beberapa bukti seperti di bawah ini dapat dikemukakan untuk menunjukkan bahwa hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari telah diterima, dipatuhi dan dihormati sebagai suatu norma hukum, seperti misalnya : a. Alat-alat perlengkapan negara, khususnya yang bertugas menangani masalahmasalah luar negeri atau internasional, menghormati kaidah-kaidah hukum intemasional yang mengatur hubungan-hubungan yang diadakannya dengan sesama alat-alat perlengkapan dari negara lain. Mereka bertindak untuk dan atas nama negaranya masing-masing. Ini berarti bahwa negaranegara itu menghormati hukum internasional tersebut. Sebagai contoh, perjanjian antara dua negara tentang garis batas wilayah, perjanjian tentang perdagangan dan lain-lainnya, mereka taati sebagai norma hukum intemasional yang mengikat dan berlaku bagi mereka. Mereka atau salah satu pihak tidak mau melanggarnya, meskipun kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan pelanggaran itu selalu terbuka. b. Perselisihan-perselisihan internasional, khususnya yang menyangkut masalah yang mengandung aspek hukum-walaupun tidak selalu- diselesaikan melalui jalur-jalur hukum internasional, seperti misalnya mengajukan ke Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Internasional dan upaya-upaya hukum lainnya. Demikian pula putusan-putusan dari badan-badan peradilan itu-diakui oleh para pihak-mengandung nilai-nilai hukum internasional, meskipun dalam praktiknya kadang-kadang tidak ditaati. Namun demikian, hal ini tidaklah mengurangi nilai hukum yang terkandung di dalamnya. 74 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional c. Pelanggaran-pelanggaran atas kaedah-kaedah hukum internasional ataupun konflik-konflik intemasional yang sering kita jumpai dalam berita-berita media massa, hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan perilaku dan tindakan-tindakan negara-negara yang mentaati hukum internasional itu. Hal serupa juga terjadi di dalam masyarakat nasional dengan tata hukum nasionalnya yang jelas dan tegas serta dilengkapi dengan aparat-aparat penegak hukumnya. Pelanggaran-pelanggaran atas hukum nasional pun hampir setiap hari dapat dijumpai serta tidak kalah jumlah maupun kualitas pelanggarannya dibandingkan dengan pelanggaran atas hukum internasional. Pelanggaranpelanggaran atas hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa hukum nasional itu tidak ada. Sudah tentu demikian pula dengan pelanggaran-pelanggaran atas hukum internasional, tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa hukum intemasional itu tidak ada. Masih lebih banyak anggota masyarakat yang mentaati hukum internasional dibandingkan dengan yang melanggarnya. d. Kaidah-kaidah hukum internasional dapat diterima dan diadaptasi sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara. Hal ini berarti bahwa negaranegara sudah menerima hukum internasional sebagai suatu bidang hukum yang berdiri sendiri yang dengan melalui cara atau prosedur tertentu dapat diterima menjadi bagian dari hukum nasional. Bahkan dalam beberapa hal, hukum internasional mau tidak mau hams diperhitungkan dan diperhatikan oleh negara-negara di dalam menyusun peraturan perundangundangan nasional mengenai suatu masalah tertentu. Sebagai contohnya, pada waktu suatu negara akan menyusun ketentuan undang-undang pidana tentang kejahatan penerbangan, negara itu tidak dapat melepaskan din dari Konvensi-konvensi Intemasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan seperti misalnya Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970 dan Konvensi Montreal tahun 1971. demikian pula dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yang merupakan norma hukum laut bam dan modem yang menggantikan kaidahkaidah hukum laut sebelumnya (Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958). Jika suatu negara meratifikasi Konvensi tersebut, hal ini tentu saja akan memaksa negara itu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum laut nasionalnya dengan isi dan jiwa Konvensi Hukum laut 1982 itu. Hukum internasional, pada dasamya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tataran intemasional. Utamanya dilakukan oleh negara sebagai salah satu subyek hukum intemasional.Sementara itu, hukum intemasional terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara- negara dalam melangsungkan hubungan antara masing-masing negara.Oleh karena itu tidaklah terlalu penting untuk mempertanyakan ada tidaknya kekuasaan tertinggi dalam hukum intemasional. Sebab tanpa adanya kekuasaan tertinggi sekalipun, kebanyakan negara mematuhi kesepakatan-kesepakatan intemasional. 75 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 3. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Pembahasan tentang tempat atau kedudukan hukum intemasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasayarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat intemasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum intemasional dan kedudukan hukum intemasional dalam keseluruhan tata hukum di lihat dari sudut praktis. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan Voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hirarkhiantara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama. Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut.Aliran yang pertama adalah aliran dualisme.Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku Volkerrecht and Landesrecht (1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivisme dari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale (1923). menurut aliran dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum intemasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum intemasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan lainnya. Hal ini di dasarkan pada alasan formal maupun alasan yang berdasarkan kenyataan.Paham dualisme ini sangat terkait dengan paham positivisme yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara. Secara historis pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Diantara alasan-alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum 76 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum intemasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara; (2) perangkat hukum itu berlainan subyek hukumnya Subyek hukum dari hukum nasional ialah orang perorangan baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subyek hukum internasional ialah Negara dan beberapa entitas lainnya; (3) sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan Pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah intemasional dan organ eksekutif, tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional; Dalam praktiknya daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum intemasional. Dalam kenyataan ketentuan hukum nasional tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dari pandangan aliran ini mempunyai beberapa akibat penting, yaitu : (1) bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional, karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari lainnya. (2) bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (renvoi) saja. (3) ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dengan demikian hukum internasional hanya berlaku setelah di transformasikan dan menjadi hukum nasional, sehingga is tidak berlaku sebagai hukum internasional. Pada paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi.Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional.Untuk paham yang seperti disebut sebagai paham "monisme dengan primat hukum nasional". Paham lain berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum internasional. Pandangan ini disebut 77 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 sebagai paham "monisme dengan primat internasional". Menurut teori monisme , keduanya sangat mungkin terjadi. Dalam pandangan monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional itu tidak lain merupakan lanjutan hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri, atau auszeres Staatsrecht. Aliran ini pernah berlaku di Jerman, yang kemudian di kenal dengan madzab Bonn (dengan tokohnya Max Wenzel). (Mochtar Kusumaatmadja, 1989, 57). Perkembangan masyarakat internasional di era global memunculkan kelompok moderat dengan teori koordinasi. Mereka menganggap bahwa HI memiliki lapangan berbeda sebagaimana hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. HI dan HN tidak bisa dikatakan terdapat masalah keutamaan. Masing-masing berlaku dalam areanya sendiri, oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah antara satu dengan lainnya. Pemahaman kelompok ini sebenarnya merupakan modifikasi dari paham teori dualisme. Menurut Anzilotti, bahwa hukum nasional ditujukan untuk ditaati sedangkan hukum internasional dibentuk dengan dasar persetujuan yang dibuat antar negara ditujukan untuk dihormati. ( John 0 Brien, dalam Jawahir Thontowi, 2001, 109). 4. Praktik Penerapan Hukum Internasional di tingkat Nasional Berlakunya hukum intemasional dalam peradilan nasional suatu negara mengacu pada doktrin "inkorporasi" dan doktrin "transformasi". Menurut doktrin inkorporasi, bahwa hukum intemasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Apabila suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat atau perjanjian apapun dengan negara lain, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Contoh negara yang menerapkan doktrin ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan beberapa negara dengan sistem AngloSaxon. Doktrin transformasi menyatakan sebaliknya, bahwa tidak terdapat hukum internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukan proses tranformasi berupa pernyataan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan. Sehingga traktat atau perjanjian internasional, tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum di pengadilan nasional sebelum dilakukannya `transformasi' ke dalam hukum nasional. (Malcolm D.Evans, 2003, 147). Doktrin inkorporasi beranggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian yang secara otomatis menyatu dengan hukum nasional. Doktrin ini lebih mendekati teori monnisme yang tidak memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sedangkan doktrin transformasi menuntut adanya tindakan positif dari negara yang bersangkutan, sehingga lebih mendekati teori dualisme. Contoh negara yang menerapkan teori ini diantaranya adalah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia 78 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional 5. Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia dan beberapa Negara Inggris Negara Inggris menganut suatu ajaran bahwa hukum internasional adalah hukum negara (international law is the law of the land). Ajaran ini lazim dikenal dengan nama doktrin inkorporasi (incorporation doctrine). Doktrin ini mula-mula di kemukakan oleh ahli hukum Blackstone pada abad ke 18 dan di rumuskan sebagai berikut : "The law of nations, wherever any question arises which is properly the object of its jurisdiction is here adopted in its full extent by the common law, and it is held to be part of the law of the land ".Inggris merupakan salah satu negara modern yang memiliki Konstitusi tidak tertulis, dan menyerahkan persoalan hubungan luar negeri sepenuhnya pada kewenangan lembaga eksekutif. (Mochtar K, 1989; Jawahir T, 2006, 83) Doktrin ini menganggap bahwa hukum internasional sebagian hukum Inggris berkembang dan di kukuhkan selama abad XVIII dan XIX dalam beberapakeputusan pengadilan yang terkenal.Dalam perkembangannya terjadi perubahan bahwa doktrin itu tidak lagi di terima secara mutlak. Penilaian daya laku doktrin dalam hukum positif yang berlaku di Inggris di bedakan antara : (1) hukum kebiasaan intemasional (customary international law); dan (2) hukum internasional tertulis (traktat, konvensi atau perjanjian). Mengenai hukum kebiasaan internasional dapat di katakan bahwa doktrin inkoorporasi ini berlaku dalam dua pengecualian, yakni : (1) bahwa ketentuan hukum kebiasaan intemasional itu tidak bertentangan dengan suatu undangundang, baik yang lebih tua maupun yang di undangkan kemudian; dan (2) sekali ruang lingkup suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah yang tertinggi, maka semua pengadilan terikat oleh keputusan itu sekalipun kemudian terjadi perkembangan suatu ketentuan hukum kebiasaan intemasional yang bertentangan. Dan ketentuan hukum kebiasaan tersebut hams di terima oleh masyarakat internasional.Apa yang di uraikan tersebut tidak berarti bahwa suatu ketentuan hukum kebiasaan intemasional begitu saja secara otomatis akan di terapkan oleh semua pengadilan di Inggris. Pengadilan di Inggris dalam persoalan yang menyangkut hukum intemasional terikat oleh tindakan / sikap pemerintah (eksekutif) untuk beberapa hal misalnya yang menyangkut pernyataan perang, perebutan (aneksasi) wilayah atau tindakan nasionalisasi. Doktrin yang berlaku dalam hukum positif di Inggris tersebut di dasarkan pada dua dalil, yaitu (1) dalil konstmksi hukum (rule of contruction) menyatakan bahwa undang-undang yang di buat oleh parlemen (Acts of Pairlement) hams di tafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional; (2) dalil tentang pembuktian suatu ketentuan hukum internasional (rule of evidence) yang berarti hukum internasional tidak memerlukan kesaksiaan para ahli di pengadilan Inggris untuk membuktikannya. Pengadilan di Inggris boleh menetapkan sendiri ada tidaknya (take judicial notice) suatu ketentuan hukum intemasional yang langsung menunjuk pada keputusan mahkamah lain, tulisan sarjana terkemuka atau sumbersumber lain sebagai bukti tentang adanya suatu ketentuan hukum intemasional. Perjanjian intemasional yang berlaku di Inggris memerlukan persetujuan parlemen 79 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 untuk pengaturan yang berlaku dalam lingkup nasional.Misalnya, pemndangan yang mengakibatkan perubahan dalam status atau garis bataswilayah negara, yang mempengaruhi hak sipil di Inggris, dan menambah beban keuangan baik secara langsung atau tidak. Amerika Serikat Doktrin inkoorporasi dianut oleh Amerika Serikat, yang menganggap bahwa hukum internasional sebagai bagian dan hukum nasional adalah Amerika Serikat. Dalam praktik di Amerika Serikat mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum perjanjian internasional yang menentukan adalah ketentuan (tertulis) konstitusi Amerika Serikat. Menurut praktik di Amerika Serikat, apabila suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian yang "self executing", maka isi perjanjian demikian di anggap menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Amerika Serikat tanpa memerlukan pengundangan melalui perundang-undangan nasional. Sebaliknya perjanjian yang tidak termasuk golongan yang berlaku dengan sendirinya (non self executing) baru di anggap mengikat pengadilan di Amerika Serikat setelah adanya perundangundangan yang menjadikannya berlaku sebagai hukum, dan tidak memerlukan persetujuan badan legislatif. Jerman Praktik di beberapa negara Eropa, misalnya di Republik Federasi Jerman menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Jerman. Bahkan ketentuan demikian lebih tinggi kedudukannya dari undang-undang (nasional) dan langsung mengakibatkan hak dan kewajiban bagi penduduk dan wilayah Federasi Jerman Sedangkan undangundang dasar Perancis merupakan hasil dari traktat atau perjanjian internasional lainnya yang telah disahkan atau di terima menurut undang-undang, sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang nasional, dengan mensyaratkan bahwa berlakunya perjanjian itu sama dengan ketentuan pemberlakuan pada pihak lain yang terikat dalam perjanjian. Belanda Kedudukan hukum internasional dalam Konstitusi Belanda didasarkan pada Konstitusi tahun 1987, dengan ketentuan bahwa parlemen memiliki hak kontrol yang kuat terhadap hukum intemasional yang akan disahkan dan berlaku di Belanda. Sedangkan kedudukan hukum perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara hierarkhis sangat jelas kedudukannya dalam hukum nasional. Dalam Konstitusi Belanda Pasal 66 disebutkan bahwa perjanjian internasional lebih utama dari hukum nasional, dengan ketentuan bahwa hanya perjanjian yang telah mendapat persetujuan dari the State-General dan the Council-State baik dalam bentuk tersurat dan tersirat. Pemerintah Belanda merasa wajib untuk selalu ikut dalam perjanjian internasional, sebagai upaya pengembangan hukum intemasional, sehingga jika terdapat pertentangan antara perjanjian internasional 80 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional yang akan diratifikasi dengan Konstitusi negaranya, maka harus mendapat persetujuan dulu dengan 2/3 suara dari the State-General. Perancis Pada Konstitusi Perancis 1958 meyatakan bahwa traktat yang telah diratifikasi dan dipublikasikan dapat berlaku sebagaimana halnya hukum nasional. Tetapi terdapat pembatasan dalam Konstitusi, bahwa untuk beberapa persoalan yang menyangkut status individu, maka ratifikasi memerlukan proses legislasi parlemen, dan memerlukan penafsiraan oleh Dewan Konstitusi, sehingga dapat digunakan oleh pengadilan lokal. (Malcolm.N.Shaw, 1997, 124). Indonesia Pelaksanaan di Indonesia pada prinsipnya mengakui supremasi hukum internasional, tetapi tidak berarti bahwa kita begitu saja menerima hukum internasional. Sikap kita terhadap hukum internasional di tentukan oleh kesadaran akan kedudukan kita dalam masyarakat intemasional yang sedang berkembang. Sebagai bagian dari masyarakat intemasional maka Indonesia mengakui keberadaan Hukum Internasional, tetapi bukan berarti hukum nasional hams tunduk pada hukum internasional. Pada praktiknya Indonesia tidak menganut teori tranformasi, tetapi lebih condong pada sistem negara-negara kontinental Eropa, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua perjanjian dan konvensi yang telah di sahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (implementing legislation). Praktik di Indonesia terkait dengan keberadaan hukum kebiasaan intemasional, belum menampakkan sikap yang tegas. Tetapi untuk beberapa hal, seperti hukum kebiasaan di laut tentang hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorial Indonesia, maka Indonesia menerima hukum kebiasaan tersebut. Sedangkan terkait dengan sikap Indonesia terhadap perjanjian internasional, didasarkan pada kepentingan Indonesia dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian intemasional tersebut. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi intemasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang.Sebelum adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 UUD 1945 ini memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untuk itu melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba menjabarkan lebih lanjut Pasal 11 UUD 1945 tersebut.( Dina Sunyowati dkk, 2011, 45) 81 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Pengaturan tentang perjanjian intemasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan UndangUndang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional.Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: (1) Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional; (2) Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; (3) Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian intemasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut; dan (4) perjanjian-perjanjian intemasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan). Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa (Full Powers). Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Tetapi penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa. (Dina Sunyowati dkk, 2011, 46) Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau Peraturan Presiden. Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan dengan Pearaturan Presiden hanya perlu pemberitahuan ke DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;kedaulatan atau hak berdaulat 82 Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional negara;hak asasi manusia dan lingkungan hidup;pembentukan kaidah hukum baru;pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Di dalam mekanisme fungsi dan wewenang, DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan DPR, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan pengaturan seperti ini, maka dapatlah Indonesia dikatakan sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa: "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undangundang atau keputusan presiden." Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dan digunakan sebaagai tuntunan di lembaga peradilan nasional tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundangundangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden.( Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa keputusan presiden diubah menjadi peraturan presiden). Dalam Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undangundang yang lebih spesifik mengenai perjanjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undangundang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undangundang yang lebih spesifik. Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang materinya mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan dan kerjasama antar propinsi atau kota. Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 83 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 6. Penutup Sumber hukum merupakan persoalan yang sangat penting untuk setiap bagian dari hukum manapun, bail( hukum nasional dan hukum internasional. Dalam penyelesaian sengketa atau persoalan-persoalan hukum, maka sumber hukum menjadi tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyelesaiakan persoalan tersebut. Berlakunya hukum internasional (dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional) atau hukum kebiasaan internasional di Indonesia didasarkan pada keterikatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan berlakunya prinsip pacta sund servada. Apabila perjanjian internasional (bilateral dan multilateral) telah disahkan dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maka sejak saat itu, hukum internasional berlaku dan menjadi hukum nasional, sehingga dapat dijadikan tuntunan / pedoman dalam penyelesaian sengketa atau persoalan hukum di peradilan nasional. DAFTAR PUSTAKA Dina Sunyowati, Enny narwati, Lina Hastuti, Hukum Internasional, Buku Ajar, Airlangga University Press, Surabaya, 2011 Dixon, Martin, Textbook on International Law, 2nd Edition, Blackstone Press Limited,Great Britain, 1993. Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional,Binacipta, Bandung, 1989. Malcol N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 Malcolm D.Evans, International Law , New Yotk, Oxford University Press, 2003 Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234 84 POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN KOMISI-KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Bunyamin Alamsyah & Uu Nurul Huda Hakim Tinggi PTA Jakarta Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung Abstrak Selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru memiliki kelebihan dan tentu kekurangan, di satu segi pembangunan insfrastruktur dan supra struktur berkembang secara pesat, namun perjalanan pemerintahan mengalami penurunan fungsi dan perannya bahkan stagnan. Oleh karena itu, terjadilah reformasi tahun 1998 dalam berbagai bidang. Sebagai jawaban menurunnya funsgi dan peran pemerintahan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945, terdapat lah pendapat dengan pembentukan organisasi barn di luar pemerintahan. Gagasan-gagsan tersebut diwujudkan dengan pembentukan komisi-komisi yang memerlukan anggaran Negara yang tidak sedikit, bahkan kadang-kadang terjadi benturan kewenangan antara komisi-komisi juga dengan lembaga pemerintahan. Pembentukan komisi-komisi tersebut tidak lepas dari politik hukum. Kata Kunci : Politik Hukum Pelembagaan, Komisi Negara, Sistem ketatanegaraan Abstract During the 32 years of the New Order government certainly has its advantages and disadvantages, in terms of the development of infrastructure and supra-structure growing rapidly, but the journey has decreased function of government and its role even stagnant. Therefore, there was the Reform of 1998 in a variety of fields. In reply funsgi decline and the role of government under the Constitution of 1945, there was an opinion with the formation of a new organization outside the government. Gagsan ideas are realized with the establishment of committees that do not require the State budget a little, sometimes a clash of authority between committees also with government agencies. Committees should not be separated from the politics of law. Keywords: Institutionalization of Political Law, Commissions of the State, State Administration System Latar Belakang Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi, yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Sebagai langkah awal reformasi hukum, maka diwujudkan dalam bentuk amandemen UUD 1945 yang Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 merupakan hukum dasar dan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Langkah ini diawali dari reformasi politik pada tahun 1998 yang kemudian disusul dengan reformasi konstitusi (UUD 1945) tahun 1999 sampai dengan 2002. Indonesia telah melakukan perubahan besar dalam bidang ketatanegaraan. Salah satu fenomena yang mengiringi transisi menuju demokrasi adalah lahirnya lembaga-lembaga negara independen ataupun komisi-komisi negara dengan dasar hukum pembentukannya yang sangat beragam. Ada komisi negara yang kewenangannya berdasarkan perintah UUD, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU), dan bahkan ada pula lembaga atau komisi yang kewenangannya berasal atau bersumber dari Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Kehadiran komisi-komisi negara ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru.1 Di camping itu, hadirnya komisi-komisi negara di Indonesia didukung oleh adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini kurang sekali diagregasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang tersedia. Perubahan-perubahan sosial politik tersebut juga telah melahirkan pergeseran paradigma dalam melihat pembedaan secara tegas ranah negara dan ranah non-negara yang menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi trias politika. Namun diakui atau pun tidak, bahwa lahirnya ide demi ide mengenai komisi negara itu masih bersifat reaktif, sektoral, dan bahkan dadakan, belum dibungkus dengan ide-ide yang komprehensif dan utuh. Ide pembaruan yang menyertai pembentukan komisi-komisi negara itu pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan idenya sesegera mungkin karena adanya momentum politik yang lebih memberi kesempatan untuk dilakukannya demokratisasi di segala bidang. Oleh karena itu, trend pembentukan komisi-komisi negara itu tumbuh 1 86 Di tingkat masyarakat umum, performance masa lalu yang tidak kapabel, menjadi dasar bagi penolakan luas atas lembaga-lembaga negara yang ada. Sementara di tingkat elit, kegagalan atau penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara di masa lalu telah melahirkan kehendak yang kuat untuk menyebarkan kekuasaan lembagalembaga yang ada baik secara horizontal-lewat penciptaan lembaga-lembaga negara independen (dibaca: komisi-komisi negara) maupun secara vertikal melalui desentralisasi. Kehendak yang kuat ini semakin mendesak karena adanya frustasi yang luar biasa di kalangan elit menyaksikan kecenderungan kegagalan dan penyimpangan fungsi lembaga-lembaga negara yang terus berlanjut menuju era reformasi, dengan harapan yang sangat kecil unyuk melakukan perubahan dari dalam lembaga negara tersebut. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara bagaikan cendawan di musim hujan, sehingga jumlahnya banyak sekali, tanpa disertai oleh penciutan peran birokrasi yang besar. Komisi-komisi yang demikian banyak malah sudah dibentuk di mana-mana. Akibatnya, bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan justru menambah inefisiensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintah menjadi semakin banyak. Kadang-kadang ada pula lembaga yang dibentuk dengan maksud hanya bersifat ad hoc untuk masa waktu tertentu Akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para peng urusnya terus menerus digaji dari anggaran pen dapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Cornelis Lay, kehadiran komisi-komisi negara dalam skala massif, dapat dilihat sebagai bagian dari dua kemugkinan sekenario besar, pertama, merupakan mekanisme penyesuaian diri atau adaptasi dalam tradisi Huntingtunion, yang dilakukan negara dalan kerangka pengaturan trias politika. Kedua, sebaliknya, merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politika dihadapan perkembangan barn dan pergeseran paradigma pemerintah.2 Setelah hampir sebelas tahun, implementasi dari perubahan UUD 1945 masih belum menemukan bentuknya yang ideal. Sistem ketatanegaraan Indonesia masih saja gamang dan mencari bentuk. Salah satunya, reformasi institusional ketatanegaraan menemukan banyak masalah dan justru menumbuhkan keraguan publik. Beberapa pihak bahkan menyuarakan agar UUD 1945 yang "asli" diadopsi kembali, meski dengan argumentasi yang tidak terlalu jelas dan cenderung emosional. Suara demikian kebanyakan disuarakan oleh kelompok senior yang mempunyai keterkaitan romantisme sejarah yang kuat dengan konstitusi kemerdekaan tersebut. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, patut dipertimbankan bahwa kehadiran komisi-komisi negara sudah mengalami inflasi lembaga. Ironisnya, kehadiran lembaga-lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan. Tugas dan fungsi mereka malah cenderung tumpang-tindih. Pola hubungan antara komisi-komisi negara belum tertata dengan baik, sehingga konflik antarlembaga pun tak terhindarkan. Justru, keberadaan komisi-komisi negara itu sangat membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan dipakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional lembaga-lembaga tersebut. Menurut Denny Indrayana, ketidakjelasan komisi negara di Indonesia karena ketiadaan konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana sebaiknya komisi negara. Akhirnya, komisi negara hanya lahir sebagai kebijakan yang reaktif-responsif, tetapi justru tidak preventif-solutif terhadap masalah kebangsaan. Lebih lanjut Denny menegaskan, di era 1990-an, Afrika Selatan dan Thailand juga bertransisi dari pemerintahan otoriter. Keduanya juga mengalami masa-masa menjamurnya komisi negara. Namun, berbeda dengan Indonesia, kedua 2 Conelis Lay, State Auxiliary, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006, hlm. 14 87 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 negara tersebut mendesain komisi negaranya secara lebih terencana dan komprehensif. UUD Afrika Selatan mengatur secara rinci tentang fungsi dan tugas komisi negara. Demikian pula di Thailand, komisi negara mendapat tempat terhormat dalam konstitusinya.3 Ryas Rasyid berpendapat, kondisi seperti ini memberi kesan Indonesia berada dalam keadaan darurat karena pelbagai institusi yang ada selama ini tidak berperan serta berjalan efektif sesuai ketatanegaraan dan konstitusi. Kebijakan ini menggambarkan betapa DPR belum mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang berada di bawah lembaga eksekutif. Di sisi lain, lembaga quasi negara adalah terobosan sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat dan pimpinan negara terhadap lembaga negara yang ada.4 Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan bahwa pembentukan komisi-komisi negara belum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal, sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain. Di samping itu, kewenangan yang diberikan kepada komisi-komisi negara sangat beragam, sehingga mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih yang menyulitkan secara praktik dalam menentukan pola hubungan antara komisi-komisi negara tersebut. Atas dasar uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai Politik Hukum Pelembagaan Komisi-komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. POLITIK HUKUM DAN KOMISI NEGARA: TINJAUAN TEORITIS Politik Hukum Definisi tentang politik hukum cukup banyak dijumpai dalam literature, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari membagi definisi politik hukum yang dikemukakan beberapa pakar menjadi dua bagian, yaitu:5 Perspektif etimologis Politik hukum dalam perspektif ini lebih dilihat secara kebahasaan. Politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, rechtspolitiek. Recht dalam bahasa Indonesia berarti hukum, sementara kata hukum berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement), ketetapan (provision), perintah (command), dan pengertian lainnya. Sementara kata politiek mengandung arti beleid, yaitu kebijakan (policy). Politik, dalam penelusuran beberapa literatur berasal dari bahasa Yunani "politica" (politika) yang berarti hubungan yang terjadi antar individu (anggota masyarakat) dalam suatu negara. Dalam hubungan (interaksi) yang resiprokal tersebut, terjadi kesepakatan-kesepakatan terhadap suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif. Dengan demikian, secara 3 4 5 88 Denny Indrayana, Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling, Kompas, 30 April 2005, hlm 5 Restorasi Meiji ala Indonesia, Kompas, 30 April 2005, hlm 5 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik' Hukum, Raj awali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 18 Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara etimologis, politik hukum adalah kebijakankebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bidang hukum, termasuk pengambilan keputusan-keputusan hukum yang bersifat kolektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak6 Definisi dari KBBI tersebut lebih melihat politik hukum sebagai blueprint terhadap sekalian kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupakan patronase bagi stakeholders dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum. Perspektif terminologis Definisi politik hukum secara terminologis, banyak diungkapkan beberapa pemikir yang mendalami kajian politik hukum sebagai berikut:7 Satjipto Rahardjo: Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara (metode) yang akan digunakan dalam upaya mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (negara). Berdasar pada definisi tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakn beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang ingin dicapai dengan system hukum yang ada (diterapkan); (2) cara-cara (mekanisme) apa yang dianggap paling baik (efektif) untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan dan bagaimana hukum hams diubah; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang dapat membantu kita memutuskan tujuan-tujuan serta cara-cara (mekanisme) untuk mencapai tujuan tersebut secara baik? Padmo Wahjono: Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi (substansi) hukum yang akan dibentuk, serta bagaimana penerapan dan penegakannya. Soedarto: Politik hukum adalah kebijakan negara via institusi-institusi negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki (yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat) untuk mencapai tujuan negara. Abdul Hakim Garuda Nusantara: Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang dalam implementasinya meliputi : Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Berdasarkan elaborasi ragam definisi politik hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah 6 7 Ibid, hlm. 26-31. Ibid. 89 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.8 Relevansi politik hukum dengan tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; Pemagaran hukum denga prolegnas dan judial review, legislative review, dan sebagainya. Komisi Negara Pembahasan mengenai komisi negara tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai lembaga negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.9 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai (1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan, ikatan (tentang mata cincin dsb); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.10 Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata'organ' diartikan sebagai berikut: "Organ adalah kelengkapan. Alat perlenglapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran 8 9 10 90 Menurut Frans Magnis-Suseno, tujuan negara adalah memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan, dan solidaritas bangsa. Apabila bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, dimana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum. Frans Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm 310-314. Firmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, Juni 2005, hlm. 29. Kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat dalam HAS Natabaya, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945, dalam Refly Harun dkk., Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konsttitusi Press, Jakarta, 2004, hlm 6061. Lihat juga dalam Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 76. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum... .......... Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (Presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti."11 Berdasarkan pengertian tersebut, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi satu sama lain sebenarnya dapat dan memang perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan Untuk memahami secara tepat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengetahui persis apa yang dimaksud dan apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara, biasanya para ahli selalu mengkaitkan dengan pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa "Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ", maksudnya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.12 Organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan atau bersifat menjalankan norma (norm applying). "These function, be they a norm-creating or 11 12 Ibid. Menurut Hans Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti yang luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat serta terpidana yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Dikatakan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "An organs, in this sense, is an individual fulfilling a spesific function". Kualitas individu itu sebagai organ ditentukan oleh fungsinya. "he is an organ because and in so for as he performs a law creating or law-applying function". Individu tersebut dapat disebut organ negara, karena is menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (law-creating) atau fungsi yang menerapkan hukum (law-applying). Di samping dalam arti yang luas, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ negara dalam arti material. Menurut konsep "material" ini, seseorang disebut "organ" negara jika dia secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (... he personally has a specific legal position). Transaksi hukum, yakni perjanjian, merupakan tindakan membuat hukum, seperti halnya keputusan pengadilan. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan juga hakim, melakukan fungsi membuat hukum, tetapi hakim adalah sebuah organ negara. Hakim adalah organ negara menurut pengertian yang lebih sempit ini karena dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, karena dia menjalankan fungsinya secara profesional dan karena itu menerima upah reguler, gaji, yang bersumber dari keuangan negara. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Rusell & Rusell, New York, 1961, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 276. 91 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction.13 Berdasarkan pengertian Hans Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit dalam hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Setidaknya ada lima pengertian organ atau lembaga negara tersebut. Pertama, dalam arti yang paling luas, (pengertian pertama) organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying; Kedua, (pengertian kedua) organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian yang pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungi law-creating dan law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau pemerintahan; Ketiga (pengertian ketiga) organ negara dalam arti lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law creating dan lawapplying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Keempat, (dalam pengertian keempat) yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kelima, untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembagalembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit atau lembaga negara dalam pengertian kelima.14 Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsinya itu is berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.15 13 14 15 92 Ibid. Suatu organ dapat dibentuk melalui pengangkatan, pemilihan atau pengundian. Perbedaan antara pengangkatan dengan pemilihan terletak pada karakter dan kedudukan hukum dari organ yang dibentuk tersebut. Suatu organ "diangkat" oleh organ yang lebih tinggi. Suatu organ "dipilih" oleh organ negara sederajat atau sejawat, yang terdiri atas individu-individu yang secara hukum berada di bawah organ yang dipilih. Suatu organ lebih tinggi dari organ lain jika organ yang disebut pertama dapat menciptakan norma-norma yang mewajibkan organ yang disebut belakangan. Pengangkatan dan pemilihan, sebagaimana yang kita definisikan, merupakan tipe-tipe ideal yang diantara keduanya terdapat berbagai macam tipe yang tidak mempunyai sebutan khusus.Dikutip juga dalam Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UH Press, Yogyakarta, 2007, hlm 79. Di dalam Bab III Konstitusi RIS dinyatakan alat-alat perlengkapan Federal RIS terdiri dari Presiden, Menteri-menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun Pasal 44 UUDS 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjend MK, Jakarta, 2006, hlm. 40-43. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, menurut Natabaya, bila dihubungkan dengan UUD 1945, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat, melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan UUD 1945 basil amandemen terdiri dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan KY. Pendapat ini didasarkan pemikiran bahwa sistem kelembagaan negara hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi, pertama, dalam bidang perundang-undangan; kedua, berkaitan dengan pengawasan; dan ketiga, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung.16 Bintan R. Saragih, misalnya, melakukan penggolongan lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.17 Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dalam arti sempit yang dapat disebut lembaga (tinggi) negara itu menurut UUD 1945 (Pasca Amandemen) ada tujuh institusi, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Mahkamah Agung (MA); (7) Mahkamah Konstitusi. Ketujuh lembaga (tinggi) negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan negara yang utama (main organs) yang lazim dipergunakan selama ini. Karena itu, agar tidak menyulitkan, Jimly mengusulkan ketujuh lembaga ini tetap disebut lembaga tinggi negara. Adapun lembaga Komisi Yudisial, menurut Jimly, kewenangannya langsung diberikan Undang-Undang Dasar tetapi tidak tepat disebut sebagai lembaga (tinggi) negara. Sebab fungsinya hanya bersifat supporting atau auxiliary terhadap fungsi utama kekuasaan kehakiman.18 Berkaitan dengan keberadaan komisi-komisi negara yang merupakan akibat gelombang baru demokrasi ini, di sejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan barn, baik yang sifatnya independen (independent regulatory agencies), maupun yang sebatas sampiran negara (state auxiliary agencies). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politica, terhadap perkembangan baru 16 17 18 Ibid. Bintan R. Saragih, Komisi-komisi Negara dalam Sistem dan Struktur Pemerintahan Terkini, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Posisi dan Peran Komisi-komisi Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah, KRHN, Jakarta, 1 Oktober 2004. Dari pembagian tersebut, menurutnya, semua lembaga negara lain yang diatur dalam UUD 1945 adalah lembaga yang memberikan dukungan kepada ketiga pembagian tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan mereka. Lihat dalam Firmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negara ... Op.Cit., hlm 107, dan lihat juga dalam Ni'matul Huda, Lembaga Negara … Op. Cit., hlm 82. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi.... op.cit., hlm. 42. Dikutip juga dalam Ni'matul Huda, Lembaga Negara… ibid, hlm. 82. 93 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 dan pergeseran paradigma pemerintahan, dari perspektif Huntingtonian, kelahiran organ-organ kekuasaan barn, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuain diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politica. Untuk menuju suatu kondisi tertib politik.19 Terminologi lembaga independen pertama kali diperkenalkan oleh Sir Douglas Hague dari Inggris dengan istilah quasi-autonomous non-governmental organization (QUANGO). Istilah QUANGO ini dipergunakan untuk menggambarkan lembaga yang terbentuk dari kecenderungan pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self-appointed bodies). Sedangkan makna lain QUANGO menurut Pemerintah Inggris adalah suatu badan yang mempunyai peran di dalam proses pemerintah nasional, tetapi bukan departemen pemerintah atau tidak merupakan bagian dari departemen pemerintah, dan yang beroperasi lebih luas atau lebih kecil dari Menteri suatu Departemen (a body has a role in the processes of national government, but is not government department or part of one, and which accordingly operates to a greater or lesser extent at arm's length from Ministers).20 Lembaga-lembaga semacam ini ada yang bersifat independen dan semi atau quasi independen sehingga biasa disebut dengan istilah independent and quasi independent agencies, committees, dan commissions. Secara teoritis, lembaga independen (selanjutnya penulis menyebut komisi negara) bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara barn yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa hams menjadi pegawai negara. Gagasan komisi negara sebenamya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, is diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Munculnya komisi negara dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya komisi negara adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrative menjadi bagian dari tugas komisi negara. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu: (1) regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervise terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan (2) advisory, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah.21 19 20 21 94 Lihat Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Society, New Haven and London, Yale University Press, 1968. Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi..., Op. Cit., hlm 10-20 Ibid. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam Constitutional and Administrative Law, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya komisi negara dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut: Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat nonpolitik. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution/alternatif penyelesaian sengketa).22 Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belakang di atas pun memiliki bentuk yang bervariasi. Gerry Stoker, dalam analisisnya mengenai perkembangan komisi negara atau yang is sebut sebagai non-elected agency di Inggris, membagi bentuk lembaga semacam ini menjadi beberapa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu (1) berasal dari mana sumber daya untuk mengadakan dan melaksanakan lembaga itu; dan (2) bagaimana cara pengisian keanggotaan serta berasal dari mana anggota lembaga itu.23 Atas kedua dasar tersebut, Stoker menyebutkan enam jenis lembaga sebagai berikut: Central government's 'arm's-length' agency, yaitu lembaga yang penyediaansumber dayanya terutama berasal dari pemerintah pusat dan keanggotaannya diisi atas perintah pemerintah pusat. Local authority implementation agency, yaitu lembaga yang penyediaan sumber dayanya terutama melalui pemerintah daerah/lokal dan pengisian keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah daerah/lokal. Public/private partnership organisation, merupakan lembaga yang dibentuk atas partisipasi badan-badan lain yang bersifat publik maupun privat. Anggotanya adalah individu-individu yang berasal dari badan partisipan. User organisation, yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari sektor publik dan komposisi anggotanya didominasi oleh para pengguna jasa. Inter-governmental forum, merupakan lembaga yang mewakili badan-badan di sektor publik dan pendanaannya berasal dari badan-badan yang berpartisipasi tersebut. Joint boards, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah daerah/lokal yang ingin berpartisipasi. 22 23 John Alder, Constitutional & Administrative Law, Macmillan Professional Masters, London, 1989, hal. 232-233. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm… 95 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Independensi lembaga-komisi negara bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antarberbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif seperti halnya di Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut ini: Some ad hoc bodies are part of the Crown and therefore have the various Crown immunities and also fall within the Official Secrets Acts. This depends firstly upon the terms of any relevant statute and failing that upon the extent to which the Crown can legally control the day-to-day activities of the body.24 Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada hakikatnya, komisi negara bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelengaraan negara dengan dibentuk dan diatur berdasarkan kebutuhan, apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan. Dengan demikian, sifat lembaga seperti ini bukan sementara atau ad-hoc melainkan permanen sepanjang dibutuhkan. Menurut Michael R. Asimov, komisi negara atau disebutnya sebagai administrative agencies, memiliki pengertian sebagai units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.25 Mengenai watak dari sebuah komisi, apakah bersifat biasa atau independen, Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi negara tersebut. Menurutnya, pemberhentian anggota komisi negara independen, hanya dapat dilakukan berdasarkan sebabsebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan. Sedangkan anggota komisi negara biasa, dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden.26 Senada dengan Asimov, dikemukakan oleh William F. Fox, Jr., bahwa suatu komisi negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh Congress. Atau, jiakalau Presiden dibatasi untuk tidak bisa secara bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi.27 Sedangkan William F. Funk dan Richad H. Seamon memberikan penjelasan, bahwa sifat independen dari suatu komisi terefleksikan sedikitnya dari tiga hal: pertama, kepemimpinan yang bersifat kolektif, bukan hanya dipimpin oleh seorang pimpinan; kedua, kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan ketiga, masa 24 25 26 27 96 John Alder, Op.Cit. hlm 232-233. Michael R. Asimov, Administrative Law, Chicago, The BarBri Group, 2002, hlm. 2. Ibid., hlm. 20. William F. Fox, Jr., Understanding Administrative Law, Danvers, Lexis Publishing, 2000, hlm. 56. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).28 LATAR BELAKANG LAHIRNYA KOMISI-KOMISI NEGARA Menurut Said Amir Arjomand, kehadiran komisi-komisi negara atau dalam istilahnya sebagai administrative organ, telah mendominasi proses pembangunan hukum (legal development) di era modem ini, khusunya dalam reformasi konstusi di beberapa negara yang mengalami proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Dominasi ini hampir terjadi di seluruh negara, mengingat begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat modern. Disebutkan oleh Arjomand salah satu kecenderungan reformasi konstitusi di berbagai negara baru-baru ini adalah: "The modern stage of political reconstruction by rational design in the age of democratic revolutions in the late 18th century, when constitution-making itself was introduced as the procedure for the elaboration of a rational design for political reconstruction, alongside parliamentary law-making as an expression of national sovereignty and the principle of separation of powers; The age of modernization in the second half of the 19th and early 20th centuries, when(authoritarian) constitutions served as instruments of state-building and rationalization of the centralized bureaucratic Rechtsstaat, and law-making by parliaments and administrative organs dominated legal development ".29 Pernyataan Arjomand di atas diperkuat oleh Fabrice E. Lehoucq, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya konsolidasi demokrasi, yang menekan kelompok status quo, bersamaan dengan hadirnya gelombang ketiga demokratisasi, dengan cara-cara institusionalisasi politik barn, dengan pembentukan sejumlah aturan main, adalah sarana untuk pembangunan ekonomi yang pro-pasar. Dalam studinya di Amerika Latin, Lehoucq menyatakan, pembentukan komisi pemilihan umum—electoral comission—yang mengisolasi diri dari keterlibatan eksekutif dan legislative telah berkontribusi besar dalam pennguatan demokrasi konstitusional. Keberhasilan Amerika Latin dalam melakukan inovasi pembentukan institusi barn, yang bebas dari intervensi eksekutif dan legislative iniliah yang kemudian dijadikan rujukan dan diadopsi oleh banyak negara di dunia.30 Di Amerika Serikat sendiri, kelahiran organ kekuasaan baru, yang kemudian dikenal dengan istilah „komisi negara' atau administrative agencies, sesungghuhnya telah dimulai dengan pembentukan Interstate Commerce Commission, yang berdiri dengan pengesahan Congress pada 1887. Kemudian dilanjutkan pada 1914, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Amerika Serikat menghendaki sebuah lembaga yang secara khusus mengatur dunia bisnis, untuk mengawasi bentuk-bentuk persaingan usaha. Maka lahirlah apa yang dinamakan dengan Federal Trade Commision. Dalam periode berikutnya, di AS bermunculan 28 29 30 William F. Funk and Richard H. Seamon, Administrative Law: Examples and Explanations, New York, Aspen Publishers, Inc, 2001, hlm. 23. Idem. Fabrice E. Lehoucq, Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and Democratization, dalam Journal International Political Science Review, 2002, Vol. 23, No. 1, hlm. 29-46. 97 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 sejumlah komisi negara independen (independent regulatory agencies). Hingga saat ini, setidaknya tercatat 30 komisi negara independen yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Menurut catatan Nixon's Independent Regulatory Commissioner Database (2005), beberapa komisi negara independen di Amerika Serikat antara lain: the Consumer Product Safety Commission, Equal Employment Opportunity Commission, Federal Communications Commission, Federal Election Commission, Federal Energy Regulatory Commission, Federal Reserve Board of Governors, Federal Trade Commission, Interstate Commerce Commission, National Labor Relations Board, National Transportation Safety Board, Nuclear Regulatory Commission, and Securities and Exchange Commission.31 Serupa dengan Amerika Serikat, kelahiran komisi-komisi negara di Inggris, bahkan sudah dimulai semenjak masa Revolusi Industri. Kemunculan badan-badan khusus di luar organ kekuasaan pokok, merupakan jawaban atas meningkatnya kompleksitas permasalahan masyarakat Inggris. Sebagai imbas dari perubahan struktur dan konfigurasi sosial dan politik, pasca-revolusi industri. Untuk memenuhi kebutuhan itu di Inggris didirikan Countryside Commission, The Office of Fair Tradding, The Commission for Racial Equality, The Helath and Safety Commision, dan sejumlah badan lainnya.32 Menurut Jimly, banyaknya tumbuh komisi-komisi yang bersifat independen merupakan gejala yang mendunia, dalam arti bukan hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat, komisi-komisi itu masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada juga yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.33 Untuk kasus di Indonesia, menurut Firmansyah Arifin, ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukan komisi-komisi negara bare yang bersifat independen, di antaranya sebagai berikut : Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada, akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yag sistemik dan mengakar dan sulit untuk di berantas. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada, karena satu atau lain halnya tunduk di atas pengaruh satu kekuatan negara atau kekuasaan lain. Ketidakmampuan lembaga-lembaga yang telah ada untuk tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi, karena persoalan birokrasi dan KKN. 31 32 33 98 Ryan C. Black, etc., Adding Recess Appointments to the President's "Tool Chest" of Unilateral Powers, dalam Journal Political Research Quarterly, Volume 60 Number 4, December 2007, hlm 645-654. Jhon Alder, Constituional and Administrative Law, Macmillan Education LTD, London, 1989, hhn 232-233 Dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 59-60. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara Pengaruh global, dengan pembentukan lembaga dinamakan auxiliary state agence atau wathchdog institutions di banyak negara yang berada dalam situasi menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasi. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan yang otoriter.34 POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN KOMISI-KOMISI NEGARA Secara historis, embrional pelembagaan/pembentukan state auxiliary agencies di Indonesia sebenarnya sudah dimulai semenjak pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada 1993. Pada mulanya, Komnas HAM hanyalah merupakan perpanjangan dari kekuasaan eksekutif, sebagaimana terlihat dari dasar pembentukannya yang menggunakan Keputusan Presiden (Keppres),35 dan seluruh anggotanya pun diangkat oleh Presiden berkuasa saat itu, Soeharto. Awalnya, komisi bentukan Soeharto ini diragukan independensi dan kredibilitasnya. Namun melihat sepak terjangnya dalam menangani dan mengungkap sejumlah kasus pelanggran HAM, serta kemampuanya membuka relasi dengan unsur-unsur masyarakat sipil, menjadikan komisi ini cukup dipercaya masyarakat.36 Catatan lain bagi Komnas HAM adalah, meski di awal pendiriannya lembaga ini rapuh secara politik maupun pijakan konstitusionalnya. Akan tetapi, institusionalisasi Komnas HAM sebagai sebuah lembaga negara baru, di luar organ kekuasaan pokok, setidaknya telah menjadi pondasi dan pilot project bagai pembentukan lembaga-lembaga serupa, pada kurun waktu sesudahnya.37 Secara massif pelembagaan komisi-komisi negara baru terjadi pasca-reformasi 1998, Komisi Negara bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tidak jarang diantara komisi-komisi tersebut saling beririsan antara satu dengan yang lainnya, dalam soal pelaksanaan kewenangan atau mandatnya saling menegasikan satu sama lain. Hingga tahun 2009, Indonesia sedikitnya telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Berikut adalah ke-delapan belas komisi tersebut: NO 1 34 35 36 37 KOMISI Komisi Yudisial DASAR HUKUM Pasal 24B UUD 1945 & Undang-undang Nomor 22/2004 Firmansyah Arifin dkk, Op.Cit. , hlm. 107. Komisi Nasional HAM pertama kali didirikan berdasar pada Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Abdul Hakim Garuda Nusantara., KOMNAS HAM: Sub-sistem dalam Sistem Perlindungan HAM, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, Oktober 2004. Cornelis Lay, Op. Cit., hlm.5. 99 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 2 Komisi Pemilihan Umum Hak ISSN : 2303-3274 Pasal 22E UUD 1945 & Undang-undang Nomor 2007 22/ 3 Komisi Nasional Asasi Manusia 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha UU Nomor 5/1999 5 Komisi Nasional Keppres. Nomor 44/2000 — Undang-undang Nomor 37/2008 6 Komisi Indonesia Penyiaran UU Nomor 32/2002 7 Komisi Pemberantasan Korupsi UU Nomor 30/2002 8 Komisi Anak UU Nomor 23/2002 Keppres. Nomor 77/2003 9 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 10 Dewan Pers UU Nomor 27/2004 (Undangundang ini dibatalkan MK secara keseluruhan) UU Nomor 40/1999 11 Dewan Pendidikan UU Nomor 20/2003 12 Lembaga Perlindungan Saksi &Korban UU Nomor 13/2006 13 Komisi Informasi Publik UU Nomor 14/2008 14 Badan Pengawas Pemilu UU Nomor 22/2007 Ombudsman Perlindungan Keppres 48/2001- UU Nomor 39/1999 & Sumber: diformulasikan dari Firmansyah Arifin, dkk (2005), Kementerian Negara PAN, dan Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kelompok DPD di MPR, (2008). Selain ke-empat belas komisi negara independen di atas, Indonesia juga memiliki sedikitnya 41 komisi negara atau badan-badan khusus, yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif (executive branch agencies). Lembaga-lembaga ini, komisioner atau anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta memberikan pertanggung-jawaban kelembagaan kepada Presiden. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 100 Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara NO KOMISI DASAR HUKUM 1 Komisi Hukum Nasional Keppres Nomor 15/2000 2 Komisi Kepolisian UU Nomor 2/2002 3 Komisi Kejaksaan UU Nomor 16/2004 Perpres. Nomor 18/2005 4 Dewan Strategis 5 Dewan Riset Nasional Keppres. Nomor 94/1999 6 Dewan Buku Nasional Keppres. Nomor 110/1999 7 Dewan Maritim Indonesia Keppres. Nomor 161/1999 8 Dewan Ekonomi Nasional Keppres. Nomor 144/1999 9 Dewan Pengembangan Usaha Nasional Komite Nasional Keselamatan Transportasi Keppres No. 165/1999 11 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Keppres. Nomor 80/2000 12 Komite Akreditasi Nasional Keppres. Nomor 78/2001 13 Komite Penilaian Independen Keppres. Nomor 99/1999 14 Komite Olahraga Indonesia Nasional Keppres. Nomor 72/2001 15 Komite Kebijakan Keuangan Sektor Keppres. Nomor 89/1999 16 Komite Standar Nasional Satuan Ukuran PP Nomor 102/2000 17 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Keppres. Nomor 12/2000 19 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan UU Nomor 25/2003 Keppres. Nomor 81/2003 20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Keppres. Nomor 54/2005 10 18 Pembina Industri Keppres. Nomor 40/1999 UU Nomor 41/1999 Keppres. Nomor 105/1999 Keppres. Nomor 181/1998 Perpres. Nomor 65/2005 101 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 102 ISSN : 2303-3274 21 Dewan Gula Nasional Keppres. Nomor 23/2003 22 Dewan Ketahanan Pangan Keppres. Nomor 132/2001 23 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Keppres. Nomor 44/2002 24 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Keppres. Nomor 151/2000 25 Dewan Pertahanan Nasional UU Nomor 3/2003 26 Badan Narkotika Nasional Keppres. Nomor 17/2002 27 Badan Nasional Penanggulangan Bencana UU Nomor 24/2007 28 Badan Pengembangan Karet Keppres. Nomor 150/2002 29 Bakor Pengembangan TKI Keppres. Nomor 29/1999 30 Badan Pengelola Gelora Bung Karno Keppres. Nomor 72/1999 31 Badan Pengelola Kemayoran Keppres. Nomor 73/1999 32 BRR Prop.NAD dan Kep. Nias Sum-utara Perpu. Nomor 2/2005 33 Badan Profesi PP Nomor 23/2004 34 Badan Pengatur Jalan Tol PP Nomor 15/2005 35 PP Nomor 16/2005 36 Badan Pendukung Pengembangan Sist em Penyediaan Air Minum Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Pening-katan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 37 Lembaga Sensor Film PP Nomor. 8/1994 Nasional Kawasan Sertifikasi Keppres. Nomor 83/1999 Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara 38 Korsil Kedokteran Indonesia UU Nomor. 29/2004 39 Badan Pengelola Puspiptek Keppres. Nomor. 43/1976 40 Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara Keppres. Nomor. 85/1999 41 Dewan Penerbangan Antariksa Nasional dan Keppres. Nomor. 132/1998 42 Lembaga Pemerintah Departemen Non- Keppres . Nomor 3/2002 jo. Keppres. Nomor103/2001 Sumber : diformulasikan dari Firmansyah Arifin, dkk (2005), Kementerian Negara PAN, dan Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kelompok DPD di MPR, (2008). Membanjirnya komisi-komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kekinian menimbulkan problem ketatanegaraan. Setidaknya telah memunculkan beragam pertanyaan, mengapa komisi-komisi tersebut kemunculannya bisa sedemikian massif? Pertama, mungkinkah jamaknya komisi-komisi negara ini merupakan bentuk kelatahan kita dalam mengelola transisi demokrasi? Sehingga setiap pembuatan undang-undang yang mengatur kepentingan khalayak umum, selalu mengamanatkan pembentukan organ-organ negara barn, untuk melakukan pengurusan kepentingan khalayak tersebut; Kedua, apakah kemunculan beranekaragam komisi ini merupakan suatau keharusan dalam menghadapi era demokrasi? Sebagai jawaban atas meningkatnya kompleksitas persolaan masyarakat modem, yang mengakibatkan lumpuh layunya organ-organ pokok negara; Ketiga, apakah kelahiran sejumlah institusi negara di luar organ pokok kekuasaan ini, sekedar menjadi instrument untuk berbagi kuasa? Seperti diketahui, pasca-reformasi banyak elemen masyarakat sipil yang turut serta merangsek masuk dalam kursi kekuasaan, sehingga diperlukan wadah yang luas untuk menampung seluruh elemen tersebut; Keempat, mungkinkah ada skenario besar di luar negara yang mendesain sedemikian rupa, pembentukan organ-organ negara di luar organ pokok kekuasan? Selama ini muncul sinyalemen, bahwa ada campur tangan kaum `fundamentalis pasar neo-liberalis' untuk mengamputasi fungsi-fungsi pokok negara, melalui pelembagaan institusi-institusi barn negara. Langkah semacam ini sebagai sebuah upaya untuk menumbuhkan public distrust pada negara, sehingga pasar lebih mendapatkan tempat di masyarakat; Kelima, atau sebenarnya, kelahiran institusi-institusi barn tersebut, sekedar luapan ungkapan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang mapan sejak lama? Sebagai jawabannya, maka perlu dibentuk lembaga-lembaga negara bare untuk menggantikannya, atau paling tidak memberikan topangan. Berdasarkan ragam pertanyaan atas menjamurnya komisi-komisi negara negara, Cornelis Lay berpandangan bahwa kelahiran komisi-komisi negara, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: pertama, keresahan negara terhadap ketidakpastian dan dan kealpaan perlindungan individu dan kelompok 103 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 marginal, dari despotisme pejabat publik, mauupun warganegara yang lain; kedua, mencerminkan sentralitas negara sebagai otoritas publik, dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar; ketiga, merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya incremental dan komplementer, terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil pemilihan gagasan trias politica.38 Menurut hemat penulis, bahwa dalam konteks seperti ini, maka politik hukum di bidang ketatanegaraan, bukan saja hams merumuskan landasan falsafah negara di dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam undang-undang, namun penafsiran terhadap norma-norma konstitusi hasil amandemen juga telah menimbulkan problema tersendiri, sebelum norma-norma dasar itu ditransformasikan ke dalam norma undang-undang. Politik hukum di bidang ketatanegaraan memerlukan pemikiran yang sungguh-sungguh terutama dalam mentransformasikan landasan falsafah negara kita sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, dan menelaah dengan sungguh-sungguh pula kerumitan pengaturan baik berkaitan dengan kewenangan, maupun hubungan antar komisi-komisi negara yang dihasilkan dari amandeman UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan di bawah Undang-Undang. Karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi dan penyelarasan terhadap komisikomisi negara, agar masing-masing komisi negara mampu berjalan secara sinergis, dalam pelaksanaan tugasnya. Penyelarasan mesti dilakukan baik di tingkat kewenangan maupun pengaturannya. Sekiranya komisi-komisi negara mana saja yang keberadaannya dapat ditiadakan, untuk kemudian mengefektifkan kewenangan dan kinreja komisi yang lain. Selanjutnya, komisi negara yang memiliki urgensi bagi pemenuhan hak-hak masyarakat, tetapi masih lemah dalam soal kewenangan, perlu diperkuat ruang lingkup dan cakupan kerjanya. Di tingkat pengaturan, perlu didesain ulang komisi-komisi negara mana saja yang pengaturannya perlu dicantumkan di konstitusi, undang-undang, atau cukup menggunakan Keppres. Pemilahan ini didasarkan pada tingkat signifikansi dan kebutuhan masyarakat akan eksistensi komisi-komisi negara tersebut. Melalui restrukturisasi, harmonisasi dan penyelarasan, diharapkan kinerja komisi-komisi negara, dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemenuhan hakhak konstitusional warganegara. Tidak sekedar menghabiskan anggaran negara yang sudah minim jumlahnya, dengan eksistensi yang antara-ada dan tiada. Untuk melakukan restrukturisasi komisi-komisi negara, perlu segera disusun blueprint lembaga negara, khususnya bagi institusi-instusi yang aturannya berada di luar konstitusi. Di dalam blueprint tersebut perlu ditegaskan bahwa komisi negara yang sebaiknya dipertahankan hanyalah komisi-komisi yang mempertegas dan memperkokoh bangunan negara hukum, yaitu komisi-komisi negara yang mendorong dan menjaga: (1) sistem peradilan yang independen dan berintegritas, bersih dari praktik mafia peradilan; (2) perlindungan hak asasi manusia; (3) kebebasan pers; dan (4) pemilihan umum yang jujur dan adil. Di samping itu, acuan kedua bagi restrukturisasi komisi negara adalah urgensinya untuk menguatkan konsep separation of powers dalam kehidupan 38 104 Ibid., hlm. 11-12. Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara bernegara. Untuk itu, diperlukan independent regulatory agencies untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modem di Indonesia, dengan model relasi saling imbang-saling kontrol yang lebih lengkap di antara lembaga-lembaga negara (state organs). Berdasarkan empat parameter syarat dasar negara hukum serta konsep pemisahan kekuasaan modem tersebut, Deny Indrayana mengusulkan komisi negara yang patut dipertahankan adalah: Komisi Yudisial; namun dengan perluasan tidak hanya kepada hakim tetapi kepada semua aparatur hukum. KY tidak hanya mengawasi hakim namun juga polisi dan jaksa. Dengan demikian, Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan tidak diperlukan lagi, tetapi hanya akan menjadi bagian dari KY. Ada baiknya, KY dijadikan institusi yang fokus bagi administrasi peradilan. Masalah rekruitmen, promosi, mutasi hingga pemberian sanksi bagi para aparat hukum adalah wilayah kerja KY yang patut dipertimbangkan. Komisi Ombudsman; lembaga ini diperlukan untuk mengawal agenda good governance. Komisi Pemberantasan Korupsi; lembaga ini penting untuk terus menjaga Indonesia yang bebas dari korupsi melalui upaya pencegahan dan penindakan hukum. Komisi Nasional HAM; yang mempunyai divisi kerja perlindungan anak dan perempuan. Artinya Komisi Perlindungan Anak serta Komnas HAM Perempuan sebaiknya tidak lagi menjadi lembaga tersendiri. Komisi Pers Indonesia; lembaga ini merupakan peleburan Dewan Pers Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia yang penting untuk menjaga prinsip kebebasan pers yang. Komisi Pemilihan Umum; lembaga ini strategis untuk mengawal pemilihan umum yang luber dan jurdil bagi hadimya sistem ketatanegaraan yang akuntabel. Di akhir tulisan ini, untuk mengembangkan politik hukum pelembagaan komisi-komisi negara diperlukan terobosan hukum dan politik untuk penguatan komisi-komisi negara melalui konstitusi, agar memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip checks and balances. Penguatan itu penting, misalnya, sebagai bentuk komitmen tegas pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komnas HAM dinaikkan status dasar hukumnya ke tingkat konstitusi. Jaminan konstitusional itu tidak hanya menambah amunisi kehidupan bagi kedua komisi negara itu, tetapi sekaligus menjadi signal yang kuat bagi peperangan melawan korupsi dan para penjahat HAM di tanah air. Peningkatan derajat beberapa komisi menjadi organ konstitusi juga strategis untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Dengan posisi sebagai organ konstitusi, komisi negara independen akan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. 105 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Di samping menguatkan komisi-komisi negara, kiranya perlu juga untuk melikuidasi komisi-komisi negara lain di luar penegasan konsep negara hukum dan fungsi transitional justice. Likuidasi ini perlu dilakukan karena alasan strategis, teknis dan politis. Secara strategis tidak jarang keberadaan suatu komisi negara hanya menambah panjang rantai birokrasi dan tumpang tindih dengan fungsifungsi lembaga negara yang lain. Secara teknis, banyaknya komisi negara yang tumpang tindih tersebut melahirkan sistem pemerintahan yang tidak efisien dan cenderung membuat defisit keuangan negara. Secara politis, banyaknya komisi negara cenderung hanya menjadi sarana antar partai politik untuk berbagi kursi kekuasaan bahkan meski seringkali mengorbankan efisiensi pemerintahan negara. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut, maka likuidasi komisi-komisi negara merupakan kebutuhan yang mendesak dengan tetap memperhatikan urgensi dan konsepsi yang benar-benar komperehensif dan kajian yang mendalam, sehingga likuidasi tersebut tidak menimbulkan problema hukum di kemudian hari. DAFTAR PUSTAKA Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988. Bintan R. Saragih, Komisi-komisi Negara dalam Sistem dan Struktur Pemerintahan Terkini, Makalah, Jakarta, 1 Oktober 2004. Conelis Lay, State Auxiliary, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun Ili April-Juni 2006. Denny Inrayana, Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Vol. 1 No. 1, Juli 2004. _____ , Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling, Kompas, 30 April 2005. Fabrice E. Lehoucq, Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and Democratization, dalam Journal International Political Science Review, Vol. 23, No. 1, 2002. Firmansyah Arifm dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, Juni 2005. Frans Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitiusi RI, Jakarta, 2006. Jhon Alder, Constituional and Administrative Law, Macmillan Education LTD, London, 1989. Michael R. Asimov, Administrative Law, The BarBri Group, Chicago, 2002. Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007. O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, Constitutional and 106 Politik Hukum Pelembagaan Komisi Komisi Negara Administrative Law, Sweet and Maxwell, London, 2001. Refly Harun dick., Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konsttitusi Press, Jakarta, 2004. Ryan C. Black, etc., Adding Recess Appointments to the President's "Tool Chest" of Unilateral Powers, dalam Journal Political Research Quarterly, Volume 60 Number 4, December 2007. Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003, Vol 18. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Society, Yale University Press, New Haven and London, 1968. William F. Fox, Jr., Understanding Administrative Law, Lexis Publishing, Danvers, 2000. 107 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 108 ISSN : 2303-3274 QUO VADIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya) Budi Suhariyanto Puslitbang Kumdil MA-RI Abstrak Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Secara normatif, pengaturan restitusi dalam hukum positif masih belum tersinergikan dengan baik. Implikasinya, dalam hal penerapannya mengalami kendala berupa ketidaksingkronan struktur hukum. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu, ketidakharmonisan substansi hukum dan ketidaksingkronan struktur hukum ini hares segera dibenahi. Pembenahan fundamental dilakukan melalui Re-Filosofi pemidanaan dengan menjadikan restitusi sebagai pidana pokok dan memberikan posisi barn bagi korban dalam sistem peradilan pidana mendatang berdasarkan filsafat restoratifjustice. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Restitusi. Abstract Restitution is a form of legal protection form for victims of victim recovery oriented. Normatively, on the positive law, restitution has not been cooperated well yet. Consequenly, the application of the restitution had a problem, specifically unsynchronized legal structure. Under the integrated criminal justice system perspective, legal structure and legal substance disharmony need to be reorganized (regulated). A fundamental arrangement will be done by rephylosophy some punishment, than make restitution become a prinsipal (main)criminal and giving a new position for the victim to the later integrated criminal justice system based on the phylosophy of restoratifjustice. Key words: legal protection, victims, restitution. A. PENDAHULUAN Merupakan sebuah keniscayaan bahwa eksistensi kejahatan pada suatu masyarakat selalu melahirkan Korban, baik yang berwujud Korban langsung (individu yang terlanggar hak-haknya oleh pelaku kejahatan) maupun Korban tidak langsung (terganggunya eksistensi sistem norma kemasyarakatan). Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Korban kejahatan selalu "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap hal-hak Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap Korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.1 Apabila sistem peradilan semakin lemah dalam memberikan penyelesaian konflik kejahatan dalam masyarakat, maka lambat laun akan terjadi degradasi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum. Sehingga tidak heran jika pihak Korban atau keluarganya beserta masyarakat melakukan tindakan "main hakim sendiri" sebagai ekspresi dari rasa kecewa terhadap minimnya perlindungan hukum terhadap Korban. Sungguh ironis, perlindungan hak-hak asasi Pelaku kejahatan mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi (pemulihan dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh Korban kejahatan. Oleh karenanya Mudzakkir2 menyatakan bahwa adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi Korban dari suatu kejahatan yang notabene tidak bersalah tidak dilindungi konstitusi. Semestinya Korban kejahatan hams dilindungi sebab pada waktu Korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, Korban dapat menentukan besar kecilnya ganti mgi yang diharapkannya. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti mgi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi.3 Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan.4 Tidak salah kiranya ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Korban kejahatan dihadapan sistem peradilan pidana seolah-olah dipersamakan dengan Korban bencana alam, eksistensinya antara "ada" (nyata dirugikan atau mengalami penderitaan) dan "tiada" (pengakuan hak-hak asasinya guna memulihkan penderitaan atau kerugiannya). Bahkan selama dalam proses peradilan pidana 1 2 3 4 110 M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankkan, Malang, Bayu Media, 2003, Hlm.69 Mudzakkir, Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHAP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011 Apalagi, dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, dimana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali kepada masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap Korban, Lihat Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, Hlm.75-76 dalam M. Arief Amrullah, Op Cit, Hlm.83 Mudzakkir, Op Cit, Hlm.4 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi berlangsung terkadang Korban kejahatan harus menjadi korban untuk kedua kalinya (re-viktimization) dalam konteks perlakuan dari penegak hukum. Kemudian setelah proses peradilan pidana selesai pun Korban kejahatan akan menjadi korban dalam konteks kemasyarakatan karena tidak jarang korban teimarginalkan (misalnya kasus kesusilaan). Dengan demikian korban mengalami penderitaan berkali-kali tanpa ada upaya pemulihan hak berupa ganti kerugian atas segala penderitaan, kehilangan dan kenestapaannya dari Pelaku kejahatan. Seiring dengan berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi). 5 Pengaturan restitusi dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki perbedaan dalam memberikan pengertian, ruang lingkup dan mekanisme dari pemberian restitusi bagi korban. Sehingga terkadang dianggap saling bertentangan. Misalnya terkait dengan hukum acara yang mengatur mekanisme pemberian restitusi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP No.44 Thn.2008) dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara. Selain itu terkait ruang lingkup kerugian yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga berbeda. Berdasarkan realitas permasalahan normatif di atas, secara law in konkreto, aparat penegak hukum dan stakeholder6 yang memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana berbeda pemahaman dalam melaksanakan pemberian restitusi tersebut. Satu pihak lebih memilih menggunakan atau menerapkan penggabungan perkara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum (derajat KUHAP lebih tinggi daripada PP No.44 Thn.2008 yang merupakan penjabaran dari UU PSK), meskipun ruang lingkup restitusinya terbatas kerugian meteriilnya. Sementara pada pihak lain menginginkan penerapan UU PSK beserta PP No.44 Thn.2008 karena menilai mekanisme tersebut dapat memberikan restitusi yang lebih besar lingkupnya daripada yang diatur oleh KUHAP. 5 6 Diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi danlatau Korban sebagaimana diatur dalam UU PSK. 111 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Persoalan-persoalan tersebut diatas menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan perspektif filsafat, teori, norma dan praktek penerapan pemberian restitusi dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban. Perspektif kefilsafatan yang di aplikasikan dalam kajian ini adalah filsafat pemidanaan dalam konteks perlindungan Korban dengan pendekatan restoratif justice. Kajian ini juga didukung dengan perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu sebagai tolak ukur analisis dalam konteks praktek penerapan pemberian restitusi. Sementara itu kajian normatif menjadi perspektif dasar dalam menguraikan kelemahan pengaturan restitusi dalam peraturan perundangundangan yang saat ini berlaku. Sebagai akhir dari kajian dan pembahasan permasalahan tersebut maka dirumuskan solusi dan rekomendasi bagi upaya perbaikan perlindungan hukum terhadap korban yang terkait dengan pemberian restitusi. Dengan demikian diharapkan secara teoritis, kajian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian secara praktis, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para praktisi (penegak hukum) dalam melaksanakan tugas perlindungan hukum terhadap korban khususnya terkait dengan pemberian restitusi. B. TINJAUAN UMUM MENGENAI KORBAN Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Para ahli7 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korban8 mempunyai definisi yang beragam mengenai korban, sebagai gambaran 7 8 1. 2. 112 Misalnya, Arif Gosita, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. (lihat dalam Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer, 2004, Hlm.64) Sementara Muladi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (lihat dalam Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.47) Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah merumuskan pengertian korban. Diantaranya adalah sebagai berikut : Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi mengenai korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakihatkan oleh suatu tindak pidana ". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian korban sebagai prang yang mengalami Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi umum maka penulis akan mengetengahkan pendapat salah satunya saja, yaitu pendapat Lilik Mulyadi.9 Beliau10 berpendapat bahwa: Dikaji dari perspektif ilmu Victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif Ilmu Victimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari Ilmu Victimologi. Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa dari perspektif Ilmu Victimologi, korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:11 Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan penerapan sanksi 3. 4. 5. 6. 9 10 11 kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga ". Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, balk fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, mendeftnisikan korban adalah "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dalam peraturan ini yang dimaksud Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Yang menurut penulis telah berhasil memberikan pengertian korban secara rinci dan cukup komprehensif. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, Bandung, Alumni, 2012, Hlm.246 Ibid 113 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta victimless crimes yaitu victimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan; Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminology political victimology dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme; Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat economic victimology; dan Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral. Berdasarkan pengertian dan definisi yang ada, selanjutnya dapat dispesifikasikan jenis Korban sesuai dengan tipologinya. Para ahli memiliki perspektif berbeda terkait pembagian tipologi Korban,12 namun secara sederhana 12 Apabila ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah (dalam Lilik Mulyadi, Op Cit, Hlm.258-260) menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu: Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara itu Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri (dalam Lilik Mulyadi, Op Cit, Hlm.258-260), yaitu: Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada din korban dan pelaku secara bersama-sama. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan, misalnya mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dart aspek pertanggungjawabannya 114 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi penulis akan mengetengahkan pendapat Sellin dan Wolfgang13 yang mengklasifikasikan jenis korban sebagai berikut: Primary Victimization, adalah korban individual. Korbannya merupakan orangperorang atau bukan kelompok Secondary Victimization. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum Tertiary Victimization. Korban merupakan masyarakat luas Mutual Victimization. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkotika, dan lain-lain No Victimization. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu delam menggunakan suatu hasil produksi. C. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum.14 Pada dasamya persoalan ketidak seimbangan hak antara korban dan pelaku ini hams dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional.15 Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap 13 14 15 terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Politicalll victims adalah korban lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajztican Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hlm.60-61 Sesuai dengan prinsip equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan-ketentuan Internasional yang memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di hadapan hukum dan jaminan atas penghormatan martabat manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, misalnya: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 115 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban hams diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Para ahli telah merumuskan argumentasi mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Berikut ini diketengahkan argumentasi para ahli hukum yang menguraikan alasan perlindungan hukum terhadap korban sangat urgen ditinjau dari beberapa perspektif. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:16 a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti mgi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:17 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (offender-centered); 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dri kepolisian); ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (victim surveys); 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatanjalanan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic power and/or public power). Sementara itu Muladi menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, yaitu:18 Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen hams ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga 16 17 18 116 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Mikan? dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, Him. 61 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, Hlm.102 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sirtem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, Hlm 176-177 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warga negara hams berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of instituonalized trust). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh raksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara hams bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara hams menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang barn (Pasal 47 ayat 1 ke 3). Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan hukum terhadap korban, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Negara dalam konteks ini hams bersikap progresif untuk menuntut Pelaku bertanggungjawab atas pemulihan Korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggungjawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat kejahatan (perspektif Korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta motivasi Pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya). 117 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil19 hingga warganya 20 tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim sendiri.21 Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial,22 negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya didasarkan oleh sebuah kontrak pelimpahan kehendak bebas dari warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap warganya. Dengan demikian apabila negara menyalahi kontrak pelayanan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara. Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban hams juga dimaknai sebagai bagian utama dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan 23 antara fenomena Pelaku kejahatan di satu sisi dengan Korban kejahatan di sisi yang lain. Dengan demikian apabila Korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara qonditio sine quanon akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi. Seringkali terungkapnya kejahatan karena adanya laporan dari Korban kepada aparat penegak hukum. Jadi apabila Korban tidak lagi diberikan perlindungan oleh hukum, kemudian Korban tidak bergairah melaporkan pada penegak hukum, maka sudah tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban sangatlah urgen bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 19 20 21 22 23 118 Keseimbangan perlakuan dan perhatian antara Pelaku dan Korban kejahatan Yang kecewa terhadap negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan Korban Seolah-olah warga sudah tidak mau diatur oleh sistem yang dimiliki negara Jean Jacques Rousseau adalah penggagas teori contract social, dalam ajarannya Rousseau mengenai masyarakat dan negara terdapat pertentangan. Di satu pihak kebebasan tiap-tiap pribadi ditonjolkan, di lain pihak kekuasaan negara ditekankan Hal terakhir ini terjadi, oleh karena menurut Rousseau dalam negaralah kehendak umum (volonte generale) terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri yang tak boleh dilanggar. Atas nama kehendak umum itu hak-hak pribadi dikorbankan. Lihat dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1982, Hlm.91 Sebagaimana dikatakan oleh Arif Gosita bahwa kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita hares mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.Lihat dalam Arif Gosita, Op Cit, Hlm.98 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT, TEORI, NORMA DAN PRAKTEK PENERAPANNYA Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Korban,24 salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi. Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway yaitu:25 1. Meringankan penderitaan korban; 2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; 3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 4. Mempermudah proses peradilan; 5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam; Adapun pengertian ganti rugi menurut Jeremy Bentham, adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.26 Sementara itu menurut Mardjono Reksodiputro:27 Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara (disini akan dinamakan kompensasi atau compensation) dan yang dibayar oleh pelaku (dinamakan restitusi atau restitution). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua. Pertama, negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan unrtuk mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan korban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa. Pada dasamya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk 24 25 26 27 Bentuk perlindungan hukum terhadap korban dapat berupa perlindungan terhadap rasa aman selama proses peradilan, mendapatkan informasi dari perkembangan kasusnya, berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan psikologis, dan hak-hak lain yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Oktarinaz Maulidi, Upaya Perlindungan bagi Korban Kejahatan Human Trafficking, dalam http ://pembaharuan-hukum.blogspot.com Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nusa media dan Nuansa, 2006, Hlm.316 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, Hlm.94 119 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Ditinjau dari perspektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, terkait dengan pengertian dan ruang lingkup restitusi. Pengaturan restitusi menurut UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam PP No.44 Thn.2008, Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yangdiberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.28 Senada dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat mendefinisikan Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, rang lingkup kerugiaan yang dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkupi kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. 29 Sementara itu ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 98 s/d 101 berbeda dengan ketiga peraturan yang disebutkan sebelumnya Ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP ini adalah ganti kerugian dalam konteks keperdataan dan pengertian ganti kerugian dalam hal ini hanya sebatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran.30 Dengan demikian kerugian immateriil tidak termasuk dalam lingkup kerugian yang dapat dituntut melalui prosedur penggabungan perkara ini, meskipun dapat dibuktikan bahwa biayabiaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dampak kejahatan.31 Kedua, terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan 28 29 30 31 120 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bukti-bukti tersebut menjelaskan penggunaannya sebagai sarana memperbaiki dan memulihkan kerugian atau kesehatan yang langsung ditimbulkan oleh kejahatan. Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pdana, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, Hlm.111. Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi restitusi, peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. 32 Sementara itu UU TPPO memiliki objek tindak pidana hanya pada tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan KUHAP mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntutkan ganti kerugian adalah semua tindak pidana. Ketiga, terkait dengan mekanisme pemberian restitusi. Menurut PP No.44 Thn.2008, dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam halpermohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan. 33 Sementara itu mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP mensyaratkan permohonan dari pihak Korban guna mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana.34 Secara teknis permohonan ganti kerugian tersebut diajukan melalui penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan pidana. 35 Apabila Hakim memutuskan mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap. 36 Keempat, terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi. UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam PP No.44 Thn.2008, Restitusi tidak memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap pelaksanaan restitusi apabila Pelaku tidak mau melaksanakan putusan atau penetapan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari Pelaku. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU TPPO yang menegaskan bahwa apabila Pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi 32 33 34 35 36 Pasal 5 ayat (2) UU PSK yang menyebutkan bahwa "hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK". Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pasal 98 ayat (1) KUHAP Pasal 98 ayat (2) KUHAP Pasal 99 ayat (3) KUHAP 121 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka terhadap Pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 37 Berdasarkan persoalan tumpang-tindihnya pengaturan mengenai restitusi terhadap Korban kejahatan sebagaimana yang tersebut di atas maka akibatnya menurut Maharani Siti Shopia, "secara yuridis formal, justru menghambat pelaksanaan restitusi dan cenderung menimbulkan masalah Baru karena tidak ada standar dan prosedur yang sama serta cenderung memunculkan ego sektoral."38 Hal ini dapat ditinjau dari perspektif praktik penerapan penegakan hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap Korban melalui pemberian restitusi yang seringkali mengalami kendala. Diantaranya adalah terkait dengan pemilihan peraturan yang digunakan dalam pemberian restitusi oleh penegak hukum dan stakeholder39 yang terkait. Jaksa dan Hakim cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara pasal 98 KUHAP dibandingkan menggunakan UU PSK sebagaimana dijabarkan dalam PP No.44 Thn.2008. Hal ini disebabkan menurut mereka mekanisme yang diatur oleh KUHAP dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel dibandingkan dengan PP No.44 Thn.2008, Restitusi yang notabene berada di bawah KUHAP.40 Meskipun akibat dari penggunaan KUHAP tersebut menyebabkan ganti kerugian yang akan didapatkan oleh Korban lebih kecil (hanya kerugian materiil saja) dibandingkan menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut (yang notabene termasuk kerugian immateriil). Sementara itu di pihak lain, LPSK lebih cenderung untuk menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut karena dinilai lebih dapat memberikan pelayanan pemberian restitusi yang lebih optimal kepada Korban. Dalam hal ini maka terjadi ketidak singkronan struktur hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap Korban melalui pemberian restitusi. Pada dasarnya kedua permasalahan (problema normatif dan praktek) di atas dapat dikaji dan dianalisis secara teoritis melalui teori sistem peradilan pidana terpadu (intergrated criminal justice). Maim dan sistem peradilan terpadu ini menurut Muladi41 adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam : 1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. 2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 37 38 39 40 41 122 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Maharani Siti Shopia, Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan, dalam http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641 diunduh pada tanggal 16 Mei 2013 pk1.09.44 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasil Rekapitulasi Laporan Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat Kerja dengan Aparat Penegak Hukum di 8 Wilayah pada Tahun 2010, dalam Lili Pintauli, Layanan Korban di LPSK.• Praktek, Tantangan dan Harapan, Makalah Presentasi pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh LPSK, Hlm.12 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Bina Cipta, 1996, Hlm. 17. 1 5 6 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi 3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Apabila diperhatikan secara seksama maka dapat disimpulkan bahwa problema normatif dan praktek dalam pemberian restitusi sebagaimana dijelaskan di atas sangat terkait dengan singkronisasi substansial dan singkronisasi struktural. Terhadap dua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, singkronisasi substansial. Sebagaimana dijelaskan dalam perspektif normatif di atas, masih ada ketidakharmonisan pengaturan mengenai restitusi. Meskipun objek yang diatur berbeda42 namun terkesan tumpang tindih dalam realitasnya ketika diinterpretasikan,43 sehingga seolah-olah menimbulkan konflik antar norma (antinomi hukum).44 Dalam menghadapi antinomi hukum, menurut Ahmad Rifa'i perlu diberlakukan asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:45 1. Lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada terdahulu; 2. Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum; 3. Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang labih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Seringkali konflik antar norma dalam hal pemberian restitusi ini dikaitkan dilema pemberlakuan UU PSK dibenturkan dengan pasal 98 KUHAP. Sebagaimana mekanisme penyelesaian antinomi berdasarkan asas preferensi diatas maka dapat katakan bahwa secara lex posterior derogat legi priori, maka UU PSK yang diutamakan karena keberadaannya lebih barn daripada KUHAP. Demikian pula secara lex specialis derogat legi generali pun juga UU PSK yang diutamakan karena secara khusus mengatur mengenai perlindungan korban. Namun secara lex superiori derogat legi inferiori, KUHAP lah yang hams diutamakan karena pengaturan restitusi dalam UU PSK ini dijabarkan dengan menggunakan PP No.44 Thn.2008 yang notabene derajatnya dibawah KUHAP. Dengan demikian kedudukan pengaturan restitusi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah ini cukup lemah jika dibandingkan dengan pasal 98 KLTHAP. Seharusnya pengaturan secara teknis 42 43 44 45 Objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi dalam hukum positif berbeda, sebagaimana penjelasan sebelumnya Pemahaman LPSK dan parat penegak hukum berbeda terkait pemberian retitusi Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas. Lihat dalam Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 87 Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Gratika, 2011, Hlm.90 Ibid. 123 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 tentang restitusi ini ditegaskan di dalam level Undang-Undang agar lebih memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, sehingga meminimalisir terjadinya disharmoni norma (ketidaksingkronan substansi hukum). Kedua, singkronisasi struktural yang terkait dengan keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa implikasi dari pengaturan norma restitusi yang dikesankan bertentangan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidaksingkronan antar struktur hukum baik yang berperan sebagai penegak hukum (Jaksa dan Hakim) maupun yang berfungsi sebagai stakeholder (LPSK). Secara teknis, ketidakserempakan tersebut menyebabkan seolah-olah terjadi tumpang tindih kewenangan dan menimbulkan benih "ego sektoral". Permasalahan ini sedapat mungkin hams segera dibenahi karena "ketidaksehatan" hubungan antar strutural hukum akan menyebabkan kerugian bagi fungsionalisasi sistem peradilan pidana pada umumnya dan secara khusus merugikan Korban. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, vitalitas sistem peradilan pidana ini sangat terkait dengan makna "sistem" yang diartikan sebagai keterpaduan yang utuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka kemungkinan terdapat (tiga) kemgian sebagai berikut: 46 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. Pada dasarnya kerugian-kerugian akibat ketidak terpaduan struktural hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut di atas, dapat diminimalisir melalui langkah-langkah koordinatif antar struktural hukum yang berwenang dalam mekanisme pemberian restitusi. Komunikasi secara institusional melalui forumforum koordinasi akan memudahkan upaya persamaan persepsi (kesepahaman) dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban melalui pemberian restitusi. Selain itu secara fundamental, pembaharuan hukum mengenai restitusi baik secara materiil maupun formil melalui revisi UU PSK ini juga sangat urgen keberadaannya dalam upaya mewujudkan harmonisasi substansi hukum dan singkronisasi struktural hukum. Penegasan mekanisme pemberian restitusi yang diinisiasi LPSK dalam bentuk Undang-Undang ini dapat mengakhiri polemik interpretasi pilihan hukum diantara struktural hukum. Selain itu secara formil diperlukan penguatan kedudukan LPSK dalam konstelasi hubungan sub sistem peradilan pidana guna meminimalisir konflik kepentingan sektoral (saling intervensi). Sebagaimana yang ada saat ini, posisi 46 124 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994. Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi LPSK hanya sebatas sebagai supporting unit dalam membantu korban berhadapan dengan proses peradilan pidana. Implikasinya, LPSK dalam mekanisme pemberian restitusi ini hanya memiliki kewenangan pemberian rekomendasi kepada penegak hukum tentang layak tidaknya Korban mendapatkan restitusi dan juga terkait dengan perhitungan jumlah restitusi yang diminta korban. Selanjutnya tergantung penegak hukum yang memutuskan restitusi tersebut dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pertimbangan Hakim berdasarkan fakta persidangan ternyata Hakim menolak restitusi maka LPSK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hukum. Sementara itu terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan restitusi korban, LPSK pun juga tidak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa eksekusi restitusi terhadap Pelaku yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar restitusi. Dengan kewenangan yang demikian maka sudah tentu perlindungan hukum terhadap Korban yang diinisiasi LPSK tidak dapat berhasil secara optimal bahkan cenderung mengalami kendala. Diantaranya terkait dengan letak geografis LPSK yang hanya di pusat (ibukota negara), sementara korban yang memerlukan restitusi ada di daerah pelosok negeri. Dengan demikian mekanisme birokratisasi pemberian restitusi47 akan menjadi permasalahan utama bagi Korban. Sehingga kemudian timbul anggapan bahwa birokratisasi restitusi melalui LPSK ini tidak simple dan kurang fleksibel, berbeda halnya ketika menggunakan penggabungan perkara dimana Korban hanya melakukan permohonan melalui Penuntut Umum sebelum tuntutan dibacakan. Dalam konteks ini restitusi via Pasal 98 KUHAP lebih sederhana dan lebih cepat serta berbiaya murah dibandingkan restitusi via LPSK. Meskipun lingkup restitusi dari pasal 98 KUHAP lebih sempit daripada yang dapat dituntut via LPSK. Selanjutnya apabila Korban menghendaki ganti kerugian immateriil setelah ganti rugi materiilnya dikabulkan oleh pengadilan melalui penggabungan perkara, Korban hams mengajukan gugatan secara perdata dengan konsekuensi penyelesaian perkara sampai dengan eksekusinya memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut diatas, menurut hemat penulis kedua konsep mekanisme pemberian restitusi, baik melalui penggabungan perkara yang didasarkan pada pasal 98 KUHAP maupun melalui LPSK berdasarkan UU PSK pada asasnya belum memenuhi asas peradilan yang baik yaitu prosedur yang sederhana, dengan waktu penyelesaian yang cepat, dan berbiaya murah. Oleh karenanya penulis mengusulkan untuk dilakukan reformulasi pengaturan restitusi. Reformulasi guna membenahi harmonisasi substansi hukum dan singkronisasi struktural hukum. Menurut penulis, pengertian restitusi sekaligus ruang lingkup restitusi hams meliputi ganti kerugian materiil maupun immateriil. Secara teknis sesuai dengan pengertian restitusi dalam UU PSK. Adapun terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi 47 Yang notabene hares melalui LPSK sebelum dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum. 125 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 adalah sesuai dengan KUHAP yaitu meliputi semua tindak pidana. Tidak perlu dipilah sebagaimana UU PSK yang saat ini berlaku dimana hams sesuai dengan keputusan LPSK. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para Korban tindak pidana yang tidak termasuk dalam keputusan LPSK dimana mereka juga memerlukan restitusi. Sedangkan terkait dengan daya paksa restitusi, menurut penulis perlu diatur sesuai dengan Pasal 50 UU TPPO yaitu ancaman berupa sanksi pidana bagi pelaku yang tidak mau membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban. Hanya saja perlu ditambahkan klausul ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi daripada TPPO disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami Korban dan berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim. Sementara itu terkait dengan mekanisme pemberian restitusi, dalam konteks reformulasi ini, sebaiknya disesuaikan dengan mekanisme KUHAP dimana Korban cukup mengajukan pada Penuntut Umum sebelum tuntutan dibacakan, tanpa melibatkan LPSK guna meminimalisir birokratisasi restitusi. Namun perlu juga diatur mengenai kemungkinan tanpa diajukan pun, Hakim dapat memutuskan Korban mendapatkan restitusi jika dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Korban mengalami kerugian dan patut untuk dipertanggungjawabankan oleh pelaku. Dalam perspektif filosofis, penulis mengusulkan untuk memasukkan restitusi sebagai salah satu pidana pokok, dalam konteks ini perlu diakomodir filsafat pemidanaan yang berorientasi pada restoratif justice.48 Restitusi dalam konteks ini penulis sebut sebagai pidana ganti rugi yang notabene merupakan salah satu bentuk pemidanaan berupa penggantian kerugian oleh Pelaku kepada Korban, terkait pertanggungjawaban pidana Pelaku atas segala akibat tindak pidananya berupa kerugian dan kenestapaan yang telah dialami Korban. Pidana ganti rugi ini akan efektif berlakunya dan lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dibandingkan ganti kerugian atau restitusi yang hanya dipandang sebagai pidana tambahan ataupun yang hanya sebagai gugatan keperdataan. Secara konseptual pidana ganti rugi ini akan menjadi suatu rezim hukum barn dimana terjadi penggabungan dimensi hukum pidana dan hukum perdata. Sebagaimana konsep pidana qishash dan diyat dalam hukum pidana Islam,49 pelaksanannya tergantung pada kehendak Korban yang notabene merupakan pihak yang dirugikan. Pada perspektif ini, pidana ganti rugi pun barn dijatuhkan 48 49 126 Restoratif justice atau keadilan restoratif saat ini sedang menjadi paradigma bare dalam penegakan hukum pidana kontemporer. Sehingga kajian terhadapnya selalu menjadi primadona bagi upaya pencarian solusi alternatif dalam mengatasi kelemahan-kelemahan sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di dalam konsep qishash dan diyat ini terkandung sifat-sifat perdata dan pidana sekaligus. Pidana qishash dan diyat itu dijatuhkan, selain karena pertimbangan yang bersifat pidana, juga dilakukan demi korban. Pelaksanaannya itu dijatuhkan, selain karena pertimbangan yang bersifat pidana, juga dilakukan demi korban. Pelaksanaannya itu sendiripun merupakan hak korban. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Angkasa, 1996, Hlm.134-135. Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi apabila dalam persidangan Korban menginginkannya, dan dapat dimungkinkan juga pidana pokok yang lain tidak perlu diterapkan jika Korban menghendaki Pelaku cukup divonis dengan pidana pokok berupa ganti kerugian. Jadi fondasi dasar dalam pemidaan tersebut adalah filsafat restoratif justice 50 dimana reparasi atau pemulihan akibat tindak pidana dapat terwujud dan hubungan antar pihak dapat terjaga pasca proses peradilan. 51 Implikasi dari filsafat pemidanaan model ini mengakibatkan perlunya rekonstruksi kedudukan Korban dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru,52 dimana Korban diberikan ruang untuk menyampaikan aspira.si hak-haknya (dengan tetap didukung oleh Jaksa Penuntut Umum namun tetap Korban lah yang memegang peranan penting) di muka persidangan sebagaimana konsep peradilan restoratif. E. PENUTUP Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban. Secara normatif, pengaturan restitusi dalam hukum positif masih belum tersinergikan dengan baik. 1mplikasinya, dalam hal penerapannya mengalami kendala berupa ketidaksingkronan struktur hukum. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana terpadu, ketidakharmonisan substansi hukum dan ketidaksingkronan struktur hukum ini hams segera dibenahi. Pembenahan fundamental dilakukan melalui ReFilosofi pemidanaan dengan menjadikan restitusi sebagai pidana pokok dan memberikan posisi baru bagi korban dalam sistem peradilan pidana mendatang berdasarkan filsafat restoratif justice. 50 51 52 Sebagaimana pendapat Bagir Manan yang mengartikan restorative justice sebagai sebuah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Restorative Justice hares juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir( Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hlm. 4. Marian Liebmann yang secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Dalam Marian Liebmann, Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007. Hlm.25. Beberapa aspek yang mendasar dalam hukum yang relevan dengan kebijakan terhadap korban adalah pengakuan eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan, member penegasan hukum bahwa pelanggaran hukum pidana (kejahatan) adalah melanggar hak-hak korban kejahatan (disamping itu juga melanggar kepentingan masyarakat dan negara), sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik dan pemberdayaan posisi hukum korban kejahatan, tanggungjawab pelanggar terhadap pemulihan dampak kejahatan, dan memasukkan restitusi sebagai bagian dari hukum pidana dan pemidanaan. Lihat dalam Mudzakkir, Posisi Hukum .......0p Cit, Hlm.407-408. 127 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 DAFTAR PUSTAKA Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer, 2004 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Rudy Rizky (eds), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir( Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Prenada Media Group, 2007 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafmdo Persada, 2007. Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nusa media dan Nuansa, 2006 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Angkasa, 1996. Lili Pintauli, Layanan Korban di LPSK: Praktek, Tantangan dan Harapan, Makalah Presentasi pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh LPSK. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik, Bandung, Alumni, 2012 M.Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankkan, Malang, Bayu Media, 2003 Maharani Siti Shopia, Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan, dalam http://www. tempo.co/read/ko lom/2013/01/24/641 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994 …………., Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007 Marian Liebmann, Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007 Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pdana, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001 …………, Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHAP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang 128 Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sirtem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Oktarinaz Maulidi, Upaya Perlindungan bagi Korban Kejahatan Human Trafficking, dalam http://pembaharuan-hukum.blogspot.com. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung, Refika Aditama, 2007. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Bina Cipta, 1996 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1982. 129 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 130 ISSN : 2303-3274 ANTARA BEZITSRECHT DAN EIGENDOMRECHT: Kajian Tentang Hak Atas Tanah Oleh Penduduk Harto Juwono 1 Dosen Universitas Indonesia. Abstrak Pada saat ini, persoalan kepemilikian tanah diantara penduduk menjadi hal yang rumit dan sering mengakibatkan terjadinya konflik, baik individual maupun kelompok (massal). Adanya ketidakjelasan status tanah memerlukan suatu kajian dengan pendekatan historis atas pengaturan hukum atas tanah, yang berubah mengikuti rezim hukum, yang mengakibatkan perubahan pada hak dan status kepemilikan tanah tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah akibat ketidakjelasan dari pemerintah dalam menerangkan rezim hukum mana yang diberlakukan pada saat ini. Sebagian besar masyarakat masih bertahan dengan pemahaman tentang hak kepemilikan (bezitzrecht) atau hak penguasaan (beschikkingsrecht) atas tanah, yang berbeda dengan konsep hak milik atas tanah (eigendom). Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan konsep hak atas tanah (eigendom) dan hak-hal atas tanah lainnya yang diberlakukan pada saat ini sehingga tidak lagi terjadi konflik mengenai hak kepemilikan atas tanah. Kata Kunci : Hak Kepemilikan (bezitzrecht), Hak Kepemilikan Atas Tanah (eigendom), Sejarah Regulasi. Abstract Nowadays, land ownership's issues become complicated and often result in conflict to nation, either individually or groups (mass). Lack of clarity of the status of the land requires a historical approach to the study of the legal regulation of land that changed following regime, which resulted in changes to the rights and status of land ownership. Results of this study concluded that the problems came out from an incomprehensive notice from the regulator/government, in order to clarify which regime used by now. Most of the people are sticking with the understanding of property rights (bezitzrecht) or tenure (beschikkingsrecht) of land, which is different from the concept of land title rights (eigendom). Therefore, the Government is expected to socialize the concept of land title rights (eigendom) and other present land rights so the conflicts will decrease or subside. Keyword : property rights (bezitzrecht), land title rights (eigendom), regulation history Pada awal bulan Oktober 1875, seorang juru lelang (vendumeester) di Batavia menolak permohonan seorang pribumi untuk mengesahkan penjualan hak pakai 1 Penulis adalah doktor ilmu sejarah, pengajar di Departemen Sejarah, Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 individu turun-temurun atas sebidang tanah yang telah lama dihuninya. Persoalan ini disampaikan kepada pemerintah melalui Residen Batavia dan diterima oleh Gubernur Jenderal untuk diputuskan. Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge meminta pertimbangan kepada Direktur Keuangan Sprenger van Eijk, atasan juru lelang tersebut, sebelum persoalan ini bisa diputuskan.2 Persoalannya berkisar pada keabsahan hak orang pribumi (inlander) atas tanah, baik yang dihuni maupun digarapnya. Menurut pandangan para ahli hukum Belanda saat itu, hak tanah orang pribumi khususnya Jawa (grondrecht van den Javaan) tidak bisa begitu saja menerima pandangan hukum Barat yang dituangkan lewat aturan-aturan perundangan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal asal-usul dan nilai-nilai yang berlaku. Jika pemerintah kolonial yang merupakan institusi tertinggi dalam sistem hukum koloni masa itu, berusaha keras untuk memutuskan persoalan di atas dengan menggunakan aturanaturan dalam hukum positif Barat, resiko yang akan muncul adalah pelanggaran hak orang pribumi atas tanah dan bisa mengarah pada terjadinya suatu kerusuhan sosial yang bersumber dari sektor agraria. 3 Tulisan ini berusaha untuk menelusuri kembali hak apa yang sebenarnya dimiliki oleh orang pribumi khususnya di Jawa dan Madura atas tanah yang mereka akui sebagai sumber kehidupan dan bernilai sacral karena terkait dengan norma-norma aturan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan akan diketahui penerapannya dan penyesuaiannya dengan penerapan hukum positif yang diawali oleh rezim kolonial dan akan diteruskan oleh pemerintah nasional. A. Kepemilikan Tanah Penduduk Kepemilikan tanah pada penduduk pribumi di Indonesia pada masa lalu telah banyak diteliti oleh para ilmuwan, baik ilmuwan asing maupun ilmuwan Indonesia sendiri. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, kepemilikan tanah menjadi objek kajian yang menarik bagi sejumlah besar ilmuwan Belanda. Terlepas dari kepentingan yang berada di balik proyek penelitian tersebut, hasil kajian mereka bisa menjadi sumber informasi dan referensi untuk ditindaklanjuti oleh para peneliti lain termasuk juga peneliti Indonesia. Berlimpahnya hasil kegiatan penelitian ini mengarah pada terjadinya polemic yang tak berakhir di kalangan para ilmuwan Belanda, khususnya di bidang ilmu hukum yang terkait dengan pengkajian sistem agraria di tanah koloni Hindia Belanda. Polemic ini kemudian menghasilkan adanya perbedaan 2 3 132 Circulaire aan de hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en Madoera, 28 October 1875, dimuat dalam Bijblad no. 2936. Bahkan ketika Parlemen Belanda disibukkan dalam pembicaraan tentang pengesahan Agrarische Wet pada tahun 1866, Menteri Koloni E. de Waal saat itu menyatakan hak tanah orang-orang pribumi masih sangat lemah dan tunduk pada aturan adat yang tidak bisa dengan mudah diabaikan oleh penerapan hukum Barat meskipun menjanjikan prospek yang lebih baik (gebrekkige grondrecht, overdriven eerbiet voor hadats inoeten wijken voor een beter stelsel). Periksa Anon,"De koloniale staatkunde tegenover het Buitenland", dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, tahun 1867, jilid 1, halaman 187. Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht pandangan, yang mengkristal dalam dua kelompok atau mazhab besar di Negeri Belanda. Kedua mazhab ini tidak bisa saling ditemukan setidaknya sampai rezim kolonial Belanda mengakhiri kekuasaannya di Indonesia, dan sering menimbulkan masalah di kalangan para pejabat administrative kolonial yang ditempatkan di Hindia Belanda ketika mereka diperintahkan untuk menjadikan dua mazhab sebagai referensi utama dalam kebijakannya. 4 Mazhab pertama dikenal sebagai mazhab Leiden, yang dipelopori oleh C. Van Vollenhoven. Dalam penelitiannya, Van Vollenhoven menyebutkan bahwa kepemilikan tanah yang dipegang oleh orang pribumi di Hindia Belanda berasal dari upaya mereka yang didorong oleh kebutuhan untuk membuka lahan. Hal ini terkait dengan perubahan sistem pengolahan tanah dari perladangan yang nomaden menjadi persawahan yang permanen. Sebagai konsekuensinya mereka yang kemudian membuka, menggarap dan akhirnya menghuni lahan tersebut dianggap sebagai pemilik tanah (primus inter pares) sekaligus pendiri pemukiman komunal. Dan situ muncul pandangan bahwa tanah merupakan milik rakyat (volksdomein).5 Sesuai dengan perkembangannya, mengingat penduduk pribumi masa itu tidak mengenal bentuk kepemilikan individu, sistem kepemilikan bertumpu pada ikatan kolektif yang menghasilkan bentuk komunal. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa lahan yang mereka garap dan huni merupakan milik bersama, dengan pembagian hasil pada scat panen. Namun demikian mereka juga berkepentingan untuk menegaskan hak atas lahan itu terhadap adanya potensi ancaman dari luar kelompok komunal tersebut, khususnya mereka yang bukan menjadi anggota kerabat besarnya. Ketika jumlah warga yang menghuni dan menggarap lahan tersebut terns bertambah, standard penilaian yang mereka terapkan atas tanah masih bertumpu pada produktivitas. Dalam perhitungannya, produksi tanah merupakan nilai tanah dan bukan luas tanah. Oleh karena itu kesuburan tanah akan lebih menentukan jenis tanah daripada lokasi atau luas lahan. Dengan 4 5 Pada umumnya kelompok Utrecht menuduh para ilmuwan di Leiden sebagai kembali pada hukum alam yang tidak lagi relevan untuk mengatur dan memerintah tanah koloni berdasarkan sistem pemerintahan modern. Salah satu tokoh Utrecht, Profesor de Louter, menyerang Van Vollenhoven dengan pendekatan positivis dianggap lebih tepat menurut aliran Utrecht untuk menganalisis dan menghasilkan kajian bidang hukum bagi tanah koloni. Periksa W.P. Heere and J.P.S Offerhaus, International Law in Historical Perspective (The Hague, 1998, Kluwer Publ), halaman xvii. Dalam hal ini apa yang dimaksud Van Vollenhoven sendiri sebenarnya bukan hak milik dalam arti eigendom seperti pengertian hukum Barat. Ia menyebutnya dengan hak pertuanan atau penguasaan (beschikkingsrecht) yang berlaku sama seperti hak ulayat. Pada prinsipnya hak ini tidak mengenal pengalihan hak (vervreemdelingen) atas tanah yang dibuka bersama. Dari situ paradigma dalam pandangan hukum adat Barat tentang hubungan hukum antara individu dan komunitasnya muncul, yaitu keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Periksa Svein Aass, "Relevansi Teori Makro Chayanov untuk kasus Pulau Jawa", dalam Sediono M.P. Tjodronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa (Jakarta, 2008, Yayasan Obor), halaman 144. 133 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 menggunakan produksi sebagai standard ukuran, nilai yang lebih tinggi akan diberikan pada lahan yang subur termasuk fasilitas pendukungnya seper ti aliran sungai. Sebaliknya lahan hutan dan tanah rumput yang luas dianggap bernilai lebih rendah dibandingkan persawahan. 6 Karena prioritas pada nilai produksi dan ikatan primordial di antara mereka yang menggarapnya, kepemilikan atau penguasaan lahan model ini tidak mengenal hal milik individu meskipun penguasaan oleh individu semakin lama bisa terjadi. Pertumbuhan jumlah warga yang terlibat mendorong pada terbentuknya pola pemukiman permanen, seiring dengan terpenuhinya kehidupan subsistensi mereka. Hal ini juga mempengaruhi pola pembagian lahan bagi masing-masing warga, yang meskipun tidak bisa melepaskan diri dari ikatan primordial, secara perlahan berhasil menegaskan hak penguasaannya (beschikkingsrecht) atas tanah yang selama ini mereka garap dan mereka huni, khususnya terhadap intervensi warga lain yang datang dari luar. 7 Bentuk kepemilikan lahan yang demikian telah memperkuat institusi primordial dalam hubungan horizontal, yaitu antara warga dan keluarga induknya. Hubungan antara anggota dan keluarga induk semakin diperkuat dengan institusionalisasi kehidupan sosial komunitas itu, yang tumbuh dalam bentuk ikatan komunal. Ketika sistem administrative diterapkan pada ikatan komunal dengan munculnya kampung atau desa, ikatan desa menjadi perwujudan ikatan horizontal. Bertolak dari sini, setiap anggota keluarga menjadi warga desa dan sistem penguasaan tanah (beschikkingsrecht) komunal diperkuat dengan pelembagaannya oleh desa, yaitu dengan adanya institusi tanah desa, lumbung desa, banda desa, dan tanah-tanah lain bagi kepentingan bersama seperti makam, rumah ibadah, dan sebagainya. Masing-masing anggota atau warga ikut bertanggungjawab mewujudkan kepemilikan komunal institusional demikian melalui penyetoran sebagian hasil produksi tanahnya kepada lembaga-lembaga sosial desa.8 6 7 8 134 Rendahnya nilai kedua asset itu karena pertimbangan manfaat bagi penggunanya. Ketika prioritas manfaat tertinggi diberikan pada sumber produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pertama bagi penggarapnya, maka tanah yang menghasilkan tanaman pangan akan mendapatkan nilai tertinggi, sebab dari situ tanah bisa menentukan kehidupan manusia. Dari sini muncul dua unsure penting dalam hukum adat mengenai tanah, yaitu sifat dan fakta. Menurut sifatnya, tanah menjadi symbol kekuasaan karena pemilik tanah akan mengendalikan mereka yang bergantung padanya. Sementara itu menurut faktanya, tanah menjadi tempat berinteraksi, sumber penghasilan dan tempat tinggal. Periksa C. van Vollenhoven, Indonesier en zijn grond (Leiden, 1932, E.J. Brill), halaman 3-4. Menurut Collenbrander, dalam pemahaman masyarakat adat tentang penguasaan tanah, hak ini sering sulit dibedakan antara hak penguasaan dan hak kepemilikan. Bagi para ahli hukum Badat Barat, kesulitan ini diperparah dengan tidak adanya data tertulis yang mendukung dan menjelaskan kewenangan mereka atas tanah. Periksa H.T. Collenbrander, Koloniale Geschiedenis, derde deel: Nederlandsch Oost Indie sedert 1816 ('s Gravenhage, 1926, Martinus Nijhoff), halaman 54. Menurut konsep van Vollenhoven, meskipun dikenal sebagai institusi sosial komunal, desa sendiri juga tidak memiliki legalitas yang kuat sebagai pemilik tanah di seluruh wilayahnya. Menurutnya, desa hanya memiliki sisa-sisa dari hak penguasaan pribumi lama (oudinheeinsche beschikkingsrecht), sehingga ketika pada suatu saat terjadi Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht Pola serupa juga muncul tetapi mengarah pada bentuk institusi yang berbeda dan akhirnya memunculkan suatu struktur kepemilikan tanah yang berlainan dengan konsep volksdomein Van Vollenhoven. Pola kedua ini oleh seorang ahli sejarah agraria G.P. Rouffaer disebut sebagai Vorstdomein, atau tanah milik raja. Rouffaer bertolak pada pandangan bahwa hanya penguasa yang memiliki tanah, sementara mereka yang menjadi kawulanya hanya meminjam atau menumpang dalam menggarap tanah penguasa demi kepentingan mendapatkan sebagian hasil produksinya. Seperti halnya konsep Volksdomein, Vorstdomein juga menunjukkan kesamaan setidaknya dalam dua hal : pembukaan lahan pertama (ontginning) oleh orang pertama yang menjadi cikal bakal pemukiman (primus inter pares) dan pengaturan penggunaan serta penguasaan lahan dengan nilai-nilai adat yang tumbuh pada komunitas itu. Mereka yang ikut menikmati lahan itu (genotsrecht) juga memiliki ikatan primordial seperti halnya yang berlaku pada prinsip Volksdomein.9 Perbedaannya terletak pada perkembangan institusi politik yang dilakukan oleh pembuka lahan (ontginner). Jika pada prinsip volksdomein, ikatan komunal berkembang secara horizontal dan bersifat lokal, pada prinsip vorstdomein ikatan komunal berkembang menjadi ikatan feodal yang vertikal, seiring dengan pertumbuhan kelompok lokal dari kelompok sosial menjadi kelompok politik, yaitu didasarkan pada praktek dan hubungan kekuasaan. Dari kelompok lokal, apakah sesuai dengan rencana pembukanya atau tergantung pada perkembangan situasi, satuan sosial tumbuh menjadi kekuatan politik yang akhirnya terlembaga dalam Riau unit administrative tradisional yang disebut kerajaan.10 Dengan bentuk institusi politik seperti kerajaan, nilai-nilai sosial yang diadopsi dan sering juga dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan seperti Islam dan 9 10 perputaran dalam pembagian tanah kembali setelah rotasi beberapa kali panen di antara warganya, institusi desa tidak mampu menolak permintaan dan mengubah kebiasaan ini. Periksa C. Lekkerkerker, Land en Volks van Java, vol L (Amsterdam, 1938, J.B. Wolters), halaman 569. Dalam bahasa Jawa atau Sunda dikenal dengan istilah yasa, yang berarti membuat atau mencipta. Dengan merujuk istilah ini, kata tanah yasan berarti adalah tanah yang dibuka. Dalam aturan adat mereka diakui bahwa hak atas pembukaan ini bukan berasal dari penguasaan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan menjadi hak tanah mereka sendiri. Periksa Willem Philip Scheuer, Het grondbezit in de Germaansche mark en de Javaansche dessa (Rotterdam, 1885, Wed. F.G. Mortelmans), halaman 243. Menurut Benedict Anderson, perbedaan antara primus inter pares rakyat dan raja adalah bahwa primus interpares pada raja tampil sebagai pendiri dinasti, bukan hanya pendiri komunitas. Sebagai pendiri dinasti, is sering melakukan suatu tindakan keras yang menghancurkan symbol-simbol dinasti lama. Ini terjadi pada Raden Wijaya di Majapahit, Raden Patah di Demak, Sutowijoyo di Mataram dan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta. Dengan menegaskan symbol-simbol kekuasaan barn, pendiri dinasti bukan hanya mendapatkan kekuasaan tetapi juga keabsahan yang tidak bisa dibantah. Hal ini tidak terjadi pada para primus inter pares yang hanya sampai pada pembentuk komunitas lokal. Periksa Benedict. G.O. Anderson, Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia (Jakarta, 2006, Equinox Publ.), halaman 39. 135 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Hindu, berubah menjadi aturan hukum. Aturan-aturan hukum ini mengatur segala aspek kehidupan sosial masyarakat yang kemudian dilengkapi dengan sanksi dan hak bagi para pelaksanannya. Sementara itu hubungan antara mereka yang kemudian dilimpahi oleh kewenangan dan kekuasaan politik, dan mereka yang wajib patuh kepadanya diletakkan pada konsep kosmologis yang bersumber pada filosofis keagamaan (kultus dewa-raja dalam Hindu, dan kalifatullah dalam Islam).11 Bertolak dari konteks ini, muncul kewenangan raja atau penguasa untuk menguasai seluruh lahan yang ada di bawah kewenangannya. Dua sumber hukum menjadi dasar dari tuntutan ini : statusnya sebagai pembuka lahan sekaligus cikal bakal daerah itu, dan dukungan filsafat-ideologis yang mewarnai hubungan kekuasaan. Berdasarkan keduanya, raja menjadi penguasa mutlak atas seluruh tanah yang ada di bawah kekuasaan politiknya (salumahing bumi, sakurebing langit, hamung narendra kang wenang murba lan misesa).12 Dengan berlandaskan pada konsep tersebut, rakyat sebagai kawulanya mengakui hak penguasaan raja ini dalam hubungan patron-klien yang bertumpu pada ikatan primordial atau ikatan feodal. Mereka merasa bahwa dengan menggarap tanah yang dianggap sebagai milik penguasa, sebagian besar hasilnya menjadi hak penguasa dan mereka harus puas dengan sisa produksinya selain ditambah dengan hak perlindungan dan berkah yang dianggap memancar dari pusat kekuasaan. Dengan demikian dalam prinsip vorstdomein terdapat ketergantungan dalam hal kepemilikan tanah, yang sepenuhnya dipegang oleh penguasa. 13 11 12 13 136 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau (Jakarta, 1985, Yayasan Obor), halaman 32-33. Pandangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konsep kosmologi yang awalnya bersumber dalam konsep kekuasaan Hindu, ketika raja menduduki posisi penting antara alam makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam hal ini sebagai titisan dewa, raja menjadi penghubung antara alam manusia dan alam di atas manusia (supranatural sphere). Dalam konteks Islam, posisi tersebut tidak berubah kecuali dalam hal penyebutan yaitu dengan gelar sebagai Kalifatullah Sayidin Panatagama Ngabdulrachman, yang memberi raja kewenangan dan kekuasaan sangat besar. Stuart Wilson and Singgih Wibisono, Javanese English Dictionary (Singapore, 2002, Periplus), halaman 246. Meskipun dalam perkembangannya muncul interpretasi yang berbedabeda mengenai ungkapan tersebut, pada prinsipnya maknanya tetap yaitu melukiskan kekuasaan mutlak raja-raja Jawa atas kehidupan kawulanya di seluruh wilayah kekuasaannya. Di era Kerajaan Mataram Islam pada abad XVI-XVII, pandangan kekuasaan ini dipertegas lagi dengan adanya tambahan gung binathara baudenda hanyakrawati wenang wisesa ing saknegari (berkuasa mutlak dan tak terbatas atas seluruh negeri, sekaligus menjadi pengendali hukum dan penguasa duniawi). Periksa G. Moedjanto,"Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan Jawa Tempo Dulu" dalam Hans Antlov and Sven Cederroth, Kepemimpinan Jawa, Perintah Alus, Pemerintahan Otoriter (Jakarta, 2001, Yayasan Obor), halaman xvii. D.H. Burger, Structural Changes in Javanese Society: the Supravillage Sphere (Cornell, 1956, Cornell University Press), halaman 29. Hubungan antara penguasa atau raja dan kawulanya dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi tradisional di Jawa ini didasarkan pada ikatan primordial yang diatur berdasarkan kewilayahan. Ketika kekuasaan raja diambil alih oleh pemerintah kolonial, praktis hak-hak Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht B. Penerapan Hukum Positif Ketika pemerintah jajahan Belanda mulai memperluas lingkup kekuasaannya dari wilayah yang telah didominasi oleh VOC pada akhir abad XVIII, mereka menjumpai bahwa dua prinsip kepemilikan tanah di atas berlaku di Jawa. Di wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan raja-raja, yaitu wilayah di luar Banten, Cirebon, Yogyakarta dan Surakarta, prinsip volksdomein lebih banyak berlaku, meskipun juga dengan sedikit sisa-sisa prinsip vorstdomein yang masih bisa ditemukan. Khususnya bagi daerah yang telah dianeksasi dari raja-raja pribumi, prinsip vorstdomein masih tersisa pada para bupati setempat, yang akhirnya dihapuskan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels ketika para bupati dijadikan pegawai pemerintah dan dimasukkan dalam korps birokrasi kolonia1. 14 Ironisnya, meskipun rezim kolonial telah melikuidasi sisa sistem vorstdomein di bawah kekuasaannya, justri sistem yang berlaku tetap dipertahankan untuk menopang kepentingannya. Preangerstelsel, yang diterapkan di Priangan sejak akhir abad XVII, dan kemudian juga Kultuurstelsel yang diberlakukan sebagai kebijakan eksploitasi agraria sejak 1830 di tanahtanah pemerintah, menunjukkan dengan jelas penerapan kembali sistem vorstdomein namun dengan pemerintah kolonial yang menggantikan peran dan posisi raja-raja. Dalam kedua sistem ini, pemerintah kolonial menjadi sponsor utama bagi eksploitasi ekonomi. Meskipun untuk memudahkan pelaksanaan kebijakannya kepemilikan tanah secara komunal di kalangan masyarakat diperkuat, prinsip itu bukan untuk mengakui kepemilikan oleh penduduk melainkan demi kepentingan produktivitas yang menguntungkan bagi tuntutan pemerintah, baik dalam bentuk hasil bumi maupun tenaga kerja (heerendiensten).15 14 15 kekuasaannya beralih kepada pemerintah Belanda termasuk juga hak pengaturan atas kepemilikan tanah kawulanya. Sebelum pemerintahannya, di bawah rezim VOC para bupati masih dipertahankan posisi dan statusnya seperti di masa kekuasaan raja-raja Jawa. Mereka bertindak dan memiliki kewenangan seperti raja-raja kecil termasuk juga dalam hal penguasaan tanah. Di bawah pemerintahan Daendels, bupati diubah statusnya menjadi bagian dari korps pemerintahan, atau dengan kata lain dijadikan sebagai pegawai pemerintah dengan gaji tetap. Perubahan status ini membawa dampak bahwa bupati tidak lagi memiliki tanah-tanah jabatan atau menjadi penguasa tanah lokal dan juga tidak berhak mendapatkan pelayanan kerja wajib dari rakyatnya. Periksa H.W. van den Doel, Het Rijk van Insulinde: Opkomst en Ondergang van een Nederlandse Kolonie (Amsterdam, 1996, Promotheus), halaman 15. Kerja wajib bersumber dari pemahaman yang muncul di wilayah raja (vorstdomein), yaitu bahwa mengingat semua yang hidup dan mati adalah milik raja (rajapati, rajakaya, rajabrana), kawula wajib mempersembahkan tenaga dan hasil kerjanya. Jika hasil kerja diwujudkan sebagian dari panen tanah, persembahan tenaga muncul dalam bentuk kerja wajib. Kerja wajib terdiri atas kerja bagi raja atau penguasa, bagi istana, bagi masyarakat dan bagi komunitasnya. Kerja bagi masyarakat dan komunitasnya sering juga disebut dengan istilah kerja bakti. Mengenai pemahaman kerja wajib sebagai pengganti upeti, bisa dilihat pada Anon, Regeling der heerendiensten op Java ('s Gravenhage, 1866, J.A. de la Vieter), halaman 4-5. 137 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Namun demikian bersamaan dengan kemerosotan produktivitas Kultuurstelsel yang diikuti oleh serangan gencar dari pihak kelompok pengusaha swasta di belakang partai liberal dalam parlemen Belanda (Staten Generaal) terhadap monopoli pemerintah, kesadaran mulai tumbuh di antara para petinggi dan politikus Belanda baik di Den Haag maupun di Batavia, bahwa kepastian hukum di tanah koloni sangat diperlukan. Hal ini penting untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan lebih lanjut sistem administrasi kolonial yang semakin mengarah pada model legal-rasional. Dengan kepastian hukum, bukan hanya terdapat batasan yang jelas antara hak dan kewajiban, melainkan juga ada penegasan dalam hubungan antara negara induk di Eropa dan tanah koloni. Akan tetapi yang paling penting dalam perubahan ini adalah bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kelangsungan eksploitasi ekonomi, yang tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga bagi kepentingan modal swasta. Meskipun sejak tahun 1818 peluang bagi investasi telah terbuka, barn pada tahun 1850an perhatian lebih besar dicurahkan ke situ. Sementara itu investasi modal swasta bukan hanya menuntut penghapusan monopoli negara melainkan juga kejelasan dalam hal hak-hak individu atas tanah dan hubungan antara penguasaan tanah dan keberadaan institusi sosial. Melalui kejelasan ini, kalangan swasta menggunakan sebagai sarana untuk menuntut penghapusan dominasi pemerintah dengan alasan memaksimalkan eksploitasi tanah koloni sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi yang selama ini terkekang oleh dominasi Kultuurstelsel.16 Setelah melewati perdebatan yang panjang sejak tahun 1848, akhirnya Parlemen Belanda memutuskan akan mengeluarkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai sumber rujukan bagi ketetapan hukum di tanah koloni. Peraturan ini dikenal dengan nama Regeerings Reglement yang diundangkan pada tahun 1854, sebagai landasan hukum tertinggi di tanah koloni. Di samping isi dari peraturan barn ini, nuansa yang muncul dengan pengundangannya menunjukkan bahwa sudah waktunya peraturan yang bertumpu pada hukum positif Barat diberlakukan di tanah koloni, mengingat semua tujuan yang dimaksudkan di atas tidak mungkin bisa terwujud tanpa menggunakan sistem hukum Barat. Oleh karena itu semua hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di tanah koloni, atau setidaknya tanah koloni memiliki peraturan yang modelnya merujuk pada perundangan di negara induk (azas konkordansi). Semua peraturan ini dinyatakan berlaku bagi semua kawula 16 138 Kritik yang semakin keras dari kalangan swasta terhadap Kultuurstelsel muncul sejak terjadinya kemerosotan produksi yang membuktikan ketidakmampuan negara mengendalikan monopolinya atas produktivitas program ini. Kasus kelaparan di sejumlah daerah yang meskipun terkait juga dengan kondisi alam digunakan sebagai sarana untuk menyerang pemerintah agar segera melepaskan monopoli dan mengakhiri Kultuurstelsel, sambil memberikan peluang semakin besar bagi investasi modal swasta. Periksa Cornelis Fasseur, The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System (Ithaca, 1992, Cornell University Press), halaman 124-125. Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht pemerintah kolonial, sedangkan penduduk pribumi diberikan kebebasan untuk mengikutinya.17 Dalam peraturan yang diterbitkan itu, pemerintah kolonial bukan hanya mengakui status klasifikasi kelompok yang menghuni tanah koloni Hindia Belanda (ingezetenen van Nederlandsch Indie), namun juga mengenai pengakuan terhadap hak orang pribumi atas tanah yang juga dilindungi oleh pemerintah kolonial. Hal ini terlihat dari pasal 62 peraturan tersebut sebagai berikut: De Gouverneur Generaal mag gene gronden verkoopen. In dit verbod, zijn niet begrepen kleine stukken gronds, bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van nijverheid. De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in huur, volgens tregels, bij algemeene verordening te stellen. Onder die gronden worden niet begrepen de zoodanige, door de inlanders ontgonnen, of als gemeene weide, of uit eenigen anderen hoofed tot de dorpen of dessa's behoorende. Volgens regels bij algemeene verordening te stellen, worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet langer dan vijf-en-zeventig jaren. De Gouverneur Generaal zorgt dat geenerlei afstand van grond inbreuk gemaakt op de rechten der inlandsche bevolking. Gubernur Jenderal tidak boleti menjual tanah. Dalam larangan ini, tidak termasuk petak-petak tanah kecil yang dimaksudkan bagi perluasan kota-kota dan desa-desa dan untuk mendirikan infrastruktur industri. Gubernur Jenderal bisa menyewakan tanah-tanah menurut aturan yang ditetapkan dalam peraturan umum. Dalam tanah-tanah ini tidak termasuk tanah-tanah yang digarap oleh orang pribumi atau sebagai lahan pengembalaan, atau karena alasan lain termasuk milik desa atau dusun. Menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan umum, tanah-tanah ini diserahkan dalam bentuk hak sewa erfpacht selama tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun. Gubernur Jenderal memperhatikan agar tidak ada pelepasan tanah yang melanggar hakhak penduduk pribumi. Ketentuan tersebut di atas, meskipun masih dalam nuansa Kultuurstelsel yang konservatif, mulai menunjukkan adanya pandangan pemerintah untuk mengakui hak-hak penduduk dan melindunginya terhadap pelanggaran. Terlepas dari aplikasinya, semangat yang berada di balik penyusunan peraturan tersebut menunjukkan adanya niat dari negara untuk mulai memperhatikan hak-hak penduduk atas tanah. Hal ini semakin jelas dalam ketentuan berikutnya : Over gronden door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofed tot de dorpen behoorende, wordt door den 17 G.J. Resink, "Conflictenrecht van de Nederlands-Indische staat in internationaalrechterlijke setting" dalam Bijdrage tot de Koloniaal Instituut (BKI), tahun 1959, jilid 115, halaman 2. Dasar pemikiran ini adalah bahwa Dewan Negara (Raad van Staat) pada tahun 1845 memutuskan dalam sidangnya bila tanah koloni Hindia bukan merupakan wilayah atau negara asing, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Belanda. Oleh karena itu adalah wajar apabila hukum yang berlaku di Kerajaan Belanda juga berlaku di tanah koloninya. 139 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Gouverneur Generaal niet beschikt dan ten algemeenen nutte, op den voet van art 77 en ten behoove van de op hoog gezag ingevoerde cultures volgens de daarop betrekkelijke verordeningen, tegen behoorlijke schadeloostelling. Grond door inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten, wordt, op aanvraag van den rechtmatigen bezitter, aan dezen in eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen, bij algemeene verordening te stellen en in den eigendomsbrief uit te drukken, ten aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeente en van de bevoegheid tot verkoop aan niet-inikanders. Verhuur of in-gebruikgeving van grond door inlanders aan niet-inlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene verordening te bepalen. Tentang tanah-tanah yang dibuka untuk digunakan sendiri oleh orang pribumi, atau sebagai lahan penggembalaan umum atau karena alasan lain termasuk milik desa, oleh Gubernur Jenderal tidak bisa dikuasai kecuali demi kepentingan umum, atas dasar pasal 77 (Regeerings Reglement) dan demi kepentingan perkebunan yang dikelola oleh penguasa menurut peraturan yang terkait, dengan pembayaran ganti rugi yang memadai. Tanah yang dikuasai hak pakainya secara individu turun-temurun oleh orang pribumi, atas permohonan pemiliknya yang sah, bisa diserahkan nkepada pemerintah hak kepemilikannya dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan umum dan dimuat dalam surat hak milik, sehubungan dengan kewajiban terhadap negara dan komunitas serta wewenang untuk menjual kepada non-pribumi. Persewaan atau penyerahan hak pakai tanah oleh orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut aturanaturan yang ditetapkan dalam peraturan umum. Dalam ketentuan ini tampak adanya dua hal penting : pemerintah mulai mengarahkan pada hak milik tanah oleh orang pribumi (eigendom), dan pemerintah tetap menegaskan kewenangannya sebagai penguasa atas tanah di seluruh wilayah koloni, termasuk juga mengorbankannya apabila memang negara atau kepentingan umum membutuhkan lahan itu. Dengan demikian, fakta yang dualistis ini mengarah pada adanya suatu sistem kepemilikan tanah dengan negara sebagai pihak yang paling dominan dalam struktur bare yang dibentuk kemudian setelah 1870. C. Perubahan menuju Hak Milik (eigendom) Meskipun Kultuurstelsel tidak mengakui kepemilikan individu atas tanah dan mengarah pada kepemilikan komunal demi kepentingan produktivitasnya, pada prakteknya sistem ini justru memperkuat institusi desa sebagai pemegang kewenangan atas tanah. Jika di masa sebelumnya desa lebih banyak bergantung pada kehendak warganya dalam hal penggarapan dan produktivitas tanah, akibat Kultuurstelsel kewenangan desa atas tanah diperkuat sementara hak individu merosot tajam.18 18 140 Salah satu kebijakan pemerintah yang memperkuat institusi desa adalah dengan merekrut para petani yang sebelum masa ini diketahui menguasai sebagian tanah desa karena faktor keturunan, diangkat menjadi kepala desa atau aparat desa. Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht Penguatan hak desa atas tanah ini tampak dari adanya kewenangan desa yang diwakili oleh aparatnya untuk menggantikan posisi individu sebagai pemegang hak penguasaan tanah dengan orang lain selama kuota produksi tanah yang wajib disetorkan kepada pemerintah dipenuhi. Dengan demikian ada empat cara desa untuk mengurangi peran individu. Pertama, ketika desa menganggap bahwa penggarap tanah itu tidak mampu memenuhi target produksi yang ditetapkan. Kedua, memaksa individu meninggalkan desa dan tidak menggantikannya dengan warga lain tetapi menjadikannya sebagai tanah desa. Ketiga, sistem dadal, yaitu menempatkan tanah yang belum dibuka langsung menjadi hak kepemilikan (bezitsrecht) desa. Keempat, desa bisa mengundang orang dari luar untuk menggarap tanah yang dinyatakan milik desa namun tetap hanya dengan hak menikmati (genootrecht) selama beberapa kali panen.19 Kondisi tersebut di atas secara perlahan menciptakan perubahan baru dalam sistem kepemilikan tanah. Meskipun kewenangan institusi desa diperkuat, konsep hak penguasaan perlahan-lahan tergeser dengan hak kepemilikan (bezitsrecht). Dalam hal ini ada dua pihak yang paling berperan : desa itu sendiri dan pendatang dari luar desa yang berpeluang untuk menguasai tanah meskipun pada mulanya hanya terbatas menikmati hasilnya (genotsrecht). Kemunculan pendatang dari luar desa otomatis telah menandai memudarnya ikatan komunal desa dan hal ini akan berpengaruh pada kepemilikan tanah lebih lanjut.20 Ketika pada tahun 1870 Parlemen Belanda mengesahkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang berlaku untuk wilayah koloninya di Jawa dan Madura, salah satu pasalnya menjamin hak-hak penduduk pribumi yang tercatat sebagai berikut: 19 20 Akibatnya dia hams bertanggungjawab pada pasokan kuota hasil bumi desanya yang ditetapkan oleh pemerintah dan statusnya, meskipun is masih membawahi petani numpang atau orang bujang yang tinggal di rumahnya, merosot menjadi abdi pemerintah daripada orang kaya desa. Namun demikian hal ini justru memperkuat desa sebagai institusi yang menjadi ketergantungan pemerintah bagi pelaksanaan Kultuurstelsel. Periksa Nicolaas Gerard Pierson, Het kultuurstelsel: zes voorlezingen (Amsterdam, 1868, P.N. van Kampen), halaman 22-23. C. Van Vollenhoven, Javaansch adatrecht : Overgedrukt uit het adatrecht van Nederlandsch Indie (Leiden, 1923, E.J. Brill), halaman 108. Menurut Van Vollenhoven semua praktek ini diijinkan oleh pemerintah dan dimungkinkan oleh sistem Kultuurstelsel. Karena tuntutan yang berlebihan dan menciptakan beban berat, banyak orang tidak lagi mampu bekerja dan memilih untuk meninggalkan desa dan mencari lahan barn yang bebas dari aturan eksploitasi tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi desa dan menguntungkan bagi aparat desa, di samping juga membuka peluang bagi orang di luar desa untuk mulai ikut mengeksploitasi tanah komunal. Meskipun hak menikmati hasil (genotsrecht) di desa sudah ada sejak pembukaan pertama lahan tanah itu, pelimpahannya kepada orang luar baru bisa terjadi setelah adanya pembagian permanen dari tanah-tanah komunal untuk digunakan oleh setiap individu warganya (gebruikrecht) dan akhirnya mengarah pada kepemilikan (bezitsrecht). Dengan demikian yang dimaksudkan pelimpahan genotsrecht sebenarnya adalah hak menggarap individu (persoonlijk gebruikrecht) dan memetik hasil, bukan memiliki tanah. Periksa M.L.M. van der Linden, De gronverhuring door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera: vastgesteld door ordonnantie van 27 Augustus 1900 (Rotterdam, 1907, Masereeuw en Bouten), halaman 134. 141 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Over gronden, door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende, wordt door den Gouverneur Generaal niet beschikt dan ten het algemeenen nut op den voet van art 77 en ten behoove van de op hoog gezag ingevoerde cultuurs volgens de daarop betrekkelijk verordeningen, tegen behoorlijk schadellostelingen. Grond, door inlanders erfelijk individueel gebruik bezeten, wordt, op aanvraag van den regelmatigen bezitter, aan dezen een eigendom afgestaan onder de noodige beperkingen, bij algemeene verordening te stellen en in den eigendomsbrief uitdrukken, ten aanzien van verplichtingen ferns den lande en de gemeente van de bevoegheid te verkoop aan niet-inlanders.21 Tentang tanah-tanah yang dibuka oleh orang pribunii untuk digunakan sendiri, apakah sebagai lahan penggembalaan atau karena alasan lain termasuk milik desa, oleh Gubernur Jenderal tidakmbisa dikuasai kecuali demi kepentingan umum atas dasar pasal 77 dan demi kepentingan tanaman yang ditanam oleh pemerintah menurut peraturan terkait untuk itu dengan ganti rugi yang memadai. Tanah yang digunakan oleh orang pribumi secara individu turun-temurun, atas permohonan pemiliknya yang sah, bisa diserahkan kepadanya menjadi hak milik dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan, ditetapkan dalam peraturan umum dan dicetak dalam surat bukti hak milik, sehubungan dengan kewajibankewajibannya terhadap negara dan masyarakat yang berwenang untuk menjualnya kepada orang non-pribumi. Dalam pasal tersebut terdapat suatu ketentuan yang menegaskan dua hal : pengakuan pada kepemilikan individu (indivueel gebruik bezeten), meskipun pada mulanya hanya terbatas pada hak pakai, dan peluang untuk menjadikannya sebagai hak milik individu secara mutlak (eigendom) termasuk menjualnya kepada orang non-pribumi, meskipun masih berada dalam batas-batas tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas, sejak tahun 1870 bisa dikatakan ada perubahan besar dalam apa yang disebut sebagai hak milik tanah bagi orang pribumi. Dengan adanya status hak milik yang jelas, hak-hak materi individu secara utuh diakui sehubungan dengan kepemilikan atas tanah oleh pemerintah, bahkan pemerintah sendiri tidak bisa melanggarnya kecuali jika kepentingan umum menuntutnya. Namun demikian proses menuju perubahan menuju hak milik bukan merupakan sesuatu yang mudah. Selain latar belakang budaya dan adat yang berbeda dengan masyarakat Barat, pada orang pribumi nilai-nilai hukum materi yang menyangkut tanah saat itu juga masih rendah, di samping nilai-nilai ikatan adat komunal masih terasa sebagai akibat dari Kultuurstelsel.22 Hal ini seperti yang tampak pada kasus yang tercantum di bagian awal tulisan ini. 21 22 142 Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1870, no. 55. Peraturan ini sebelunmya dikenal sebagai UU tanggal 6 April 1870 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Belanda tahun 1870 nomor 71. Sulitnya mengikis sisa-sisa adat Kultuurstelsel ini bersumber pada tradisi budaya yang tumbuh dalam masyarakat Jawa tradisional. Gubernur Jenderal, kemudian Menteri Koloni, J.C. Baud menyatakan bahwa sistem kepemilikan lahan komunal yang ditopang oleh kerja bersama seperti gotong royong sangat sesuai bagi pengembangan Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht Salah satu kendala yang pertama-tama menghambat penyesuaian hak orang pribumi atas tanah adalah bahwa selain nilai-nilai adat, hak atas tanah pribumi juga diatur dengan nilai-nilai yang dimuat dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, setidaknya ada dua jenis tanah yang berlaku: tanah milik penguasa Islam dengan penduduk yang tinggal di atasnya atau menggarapnya dan memetik hasilnya, serta tanah yang menjadi milik individu. Hukum Islam mengakui bahwa mereka yang mengaku memiliki tanah akan tetap diakui apabila membayar upeti kepada penguasa, sebagai bukti ketundukkannya sementara penguasa akan melindungi dirinya dan hak-haknya.23 Bersama dengan sistem adat yang berlaku, hukum Islam di atas diberlakukan terutama pada tanah-tanah yang dikuasai oleh raja-raja Jawa. Namun demikian setelah pemerintah Belanda menganeksasi wilayah mereka, sistem tersebut ternyata tetap dipertahankan dan pemerintah kolonial cenderung menggantikan status raja. Kultuurstelsel, dan juga Agrarische Wet 1870 yang meskipun menghapuskan prinsip dasar Kultuurstelsel, tetap menegaskan adanya dua pemilik tanah : penguasa dan individu sebagai rakyat. Mengingat dalam hukum Barat yang diterapkan oleh Belanda melalui hukum perdata (Bergerlijke Wet) tujuan pemerintah selain untuk menguasai tanah tak bertuan sebagai milik negara (staatsdomein) juga bermaksud untuk melindungi penduduk atas hak-haknya, pemerintah bermaksud memberikan kepastian hukum. Satu-satunya cara adalah dengan memberikan penegasan tentang hak milik (eigendom recht) yang akan memudahkan pencapaian tujuan tersebut sekaligus melakukan pendataan bagi kepentingan pembayaran pajak tanah sebagai pengganti upeti atau bentuk sewa tanah.24 23 24 Kultuurstelsel dan akhirnya kebijakan eksploitasi ekonomi agraris permanen pemerintah kolonial, daripada kerja bebas dan kepemilikan tanah individu. Menurut Baud sistem ekonomi bebas ini tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jawa. Periksa Gerardus Hubertus van Soest, Geschiedenis van het Kultuurstelsel, vol. 3 (Rotterdam, 1871, Nijgh en van Ditmar), halaman 75. Beberapa ahli hukum Belanda berdebat mengenai hal ini. Ada sekelompok orang yang percaya bahwa sistem yang dianut orang pribumi, terutama di kalangan rajaraja Jawa, bertumpu pada hukum Islam khususnya dalam mengatur tanah. Sementara itu ada yang mengatakan merupakan campuran (mengelmoe) antara sistem kerajaan Hindu dan Islam. Kelompok ketiga justru berpendapat bahwa aturan itu bersumber dari nilai-nilai tradisional ash masyarakat pribumi. Tetapi pada prinsipnya mereka sepakat bahwa kepemmilikan tanah tidak bisa dilepaskan dengan penguasaan atas hak kedaulatan untuk memerintah. Periksa Wop van W. Tadama, Indische brieven van Mr. Wop over koloniale hervorming : proeven van wetsontwerpen voor radikale, geleidelijke en konservatieve hervormers ('s Gravenhage, 1866, Martinus Nijhoff), halaman 18. Bentuk upeti lama (schatting) yang merupakan warisan sistem raja-raja dan dilestarikan oleh VOC, digantikan dengan landrent atau sewa tanah yang diterapkan oleh penguasa Inggris di Jawa pada tahun 1813. Dalam konsep landrent, Raffles telah mendahului dengan mengikuti sistem yang berlaku di Inggris bahwa semua tanah merupakan milik raja dan rakyat sebagai kawula hanya menyewanya. Oleh karena itu dalam sistem ini, hak milik tanah rakyat sama sekali tidak diakui. Pemerintah kolonial dengan Kultuurstelsel tidak menghilangkan landrent meskipun hak kepemilikan komunal diakui. Baru pada tahun 1873 pemerintah mulai 143 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Akan tetapi langkah yang diambil tidak begitu mudah mengingat pemahaman hak milik dalam sistem hukum Barat dan pandangan orang pribumi berbeda. Bagi orang pribumi, hak pakai dan hak huni yang selama ini mereka gunakan dianggap sudah mewakili hak milik, sementara menurut hukum Barat keduanya belum mewakili hak milik mutlak. Untuk mengarah pada hak milik mutlak, kedua hak tersebut bersama dengan sejumlah hak lain yang muncul dari produktivitas tanah (seperti hak panen, hak petik, hak garap) diakui sebagai hak paten (zakelijk rechten). Dengan pengakuan ini, pemerintah bisa membuat aturan-aturan dan bahkan larangan bagi pengalihan hak (vervremden) dari orang pribumi kepada orang non-pribumi, dengan maksud untuk melindungi orang pribumi dari resiko kehilangan haknya. 25 Menurut pandangan pemerintah kolonial, hak paten yang diberikan kepada orang pribumi ini bisa disebut sebagai hak kepemilikan (bezitsrecht). Di samping mendapatkan lewat proses di atas, hak kepemilikan ini berdadsarkan ketentuan yang ada bisa didapatkan lewat 1. Pembukaan lahan (ontginning) dan mendaftarkannya kepada petugas pemerintah, sehingga lahan yang dibuka tidak lagi diakui sebagai hak pakai seperti dahulu melainkan hak kepemilikan. 2. Pemberian hak atas lahan tertentu oleh pemerintah dengan status hak kepemilikan.26 Akan tetapi selain persoalan di atas, pemerintah masih menghadapi persoalan lain yang merupakan warisan dari sistem kepemilikan komunal periode sebelumnya. Setidaknya diperlukan waktu lima belas tahun oleh pemerintah untuk menghapuskan kepemilikan komunal ini, termasuk kepemilikan oleh desa dan keluarga yang masih secara utuh. Baru pada tahun 1885, pemerintah kolonial akhirnya menyatakan bahwa hak kepemilikan komunal di Jawa dan Madura tidak lagi berlaku dan diganti dengan hak kepemilikan individu yang bersifat turun temurun.27 Dalam ketentuan tersebut, sejumlah syarat diperlukan yaitu : a. Minimal tiga perempat dari pemegang hak pakai atas tanah menyetujui perubahan dan cara pembagiannya. b. Setiap pemegang hak pakai tanah memiliki andil dalam kepemilikan individu tersebut c. Bila ada sebagian lahan yang digunakan sebagai tanah jabatan, apakah permanen atau bergantian, oleh kepala desa atau aparat desa, lahan itu tidak ikut dibagi namun setelah dikurangi andil untuk tanah tersebut. 25 26 27 144 memperhitungkan tentang proses pengakuan hak dengan mengeluarkan aturan verponding. Lihat Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1872 nomor 66. Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1875 no. 179. Dengan keluarnya peraturan ini, yang dianggap berlaku surut, semua kesepakatan yang telah mengalihkan hak-hak itu selamanya dari orang pribumi kepada non-pribumi, dinyatakan batal demi hukum (van rechtswege nietig). Staatsblad van Nederlangsch Indie over het jaar 1874 no. 78. Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1885 no. 102. Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht Dalam proses ini, tanah jabatan yang sering digunakan sebagai pengganti gaji bagi kepala desa dan aparat desa, muncul dan tetap dipertahankan dibandingkan dengan tanah komunal lainnya seperti banda desa, kas desa, lumbung desa, dan sebagainya yang berpeluang mengalami pengurangan.28 Selain itu perubahan lain yang terjadi dalam prose situ adalah keterlibatan aparat pemerintah. Dalam pasal 3 peraturan tersebut, residen memiliki kewenangan untuk menentukan lugs tanah jabatan seiring dengan meluasnya kontrol pemerintah atas institusi desa. Di samping kewenangan tersebut, residen juga berhak membatalkan pembagian jika dianggap berpotensi konflik dan membentuk suatu komisi yang terdiri atas aparat Eropa dan pribumi untuk melakukan penyelidikan tentang pembagian tanah tersebut jika dipandang perlu. Sementara itu mengenai hak milik mutlak (eigendomrecht) dalam arti pemahaman hukum Barat, yang diharapkan oleh pemerintah kolonial bisa dimiliki oleh penduduk pribumi, tidak mudah diwujudkan. Meskipun di Jawa dan Madura tidak terdapat ikatan komunal seperti yang berlaku di luar Jawa (tanah marga, tanah ulayat, tanah adat), namun demikian konsep tersebut masih sedikit dipahami dan popular di kalangan masyarakat pribumi.29 Namun demikian, sebagai dampak lebih lanjut dari Agrarische Wet tahun 1870, pemerintah kolonial memberikan peluang untuk mengarah pada hak milik mutlak tersebut. Peluang ini muncul pada tahun 1872 ketika sebuah peraturan dikeluarkan yang pada pasal 1 tercantum sebagai berikut: Elk inlander, die den door hem krachtens erfelijk individueel gebruiksregt bezeten grond, overeenkomstig de vierde bepaling der wet van 9 April 1870 (Indische Staatsblad no. 55) in eigendom wenscht to verkrijgen, moet zich tot uitwijzing van zijn gebruiksregt, met een verzoekschrift wenden tot den president van den landraad, binnen welke gebied de grond gelegen is, onder overlegging van een meetbrief, en voor zoover het gronden betreft waarvan geen landrente of gelijksooritge belasting verschuldig is, ook van een taxatie brief.30 Setiap orang pribumi yang ingin mendapatkan hak milik atas tanah yang olehnya telah dikuasai berdasarkan hak pakai individu turun-temurun, sesuai dengan ketentuan keempat dari UU tanggal 9 April 1870 (Lembaran Negara no. 55), harus menghadap kepada pimpinan pengadilan untuk menunjukkan 28 29 30 Lembaga-lembaga ini bukan hanya memenuhi kebutuhan bersama baik di tingkat pemerintahan desa maupun social-komunal, seperti perayaan desa, syukuran setelah panen, dan sebagainya, melainkan juga berkaitan dengan kebutuhan keagamaan, seperti mengatur subsidi bagi rumah ibadah, pembayaran zakat dan sebagainya. Dutch East Indies, Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera, vol. 9 (Batavia, 1912, Landsdrukkerij), halaman 236. Salomon van Deventer, Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, derde deel (Zalt Bommel, 1866, Joh. Noman en Zoon), halaman 235. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya, menurut Van Deventer, adalah rakyat selalu meraasa meminjam tanah, baik dari raja maupun dari komunitasnya. Nilai -nilai moral yang tinggi mencegah mereka untuk menegaskan haknya di depan rajanya atau masyarakatnya, dengan resiko sanksi moral atau hukum. Staatsblad van Nederlandsch Indie 1872 no. 117. 145 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 hak pakainya dengan sebuah surat permohonan, di tempat tanahnya berada, dengan menyodorkan sebuah surat ukur dan sejauh menyangkut tanah-tanah yang tidak dibebani dengan pajak tanah atau pajak serupa, juga dengan surat penafsiran. Dalam ketentuan itu, persoalan hak milik (eigendom) menjadi kewenangan kepala pengadilan setempat (landraad). Dengan demikian status hak milik memiliki dasar keputusan hukum yang diakui oleh pengadilan, bukan oleh pemerintah daerah (gewestelijk bestuur). Dan pasal tersebut, apabila permintaan itu dikabulkan, pengadilan (landraad) akan mengeluarkan bukti hak milik (acte van eigendom) atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang kemudian didaftarkan untuk dicatat dan disesuaikan dengan kewajiban pemiliknya, seperti pembayaran pajak. Tentang pembayaran pajak ini, pasal 21 dari peraturan tersebut menetapkan: De gronden, die krachtens dit besluit in eigendom verkregen worden, zijn, voor zoover daarvan geen landrente of gelijksoortige belasting verschuldigd is, onderworpen aan de belasting der verponding. Tanah-tanah yang berdasarkan keputusan ini mendapatkan status hak milik, sejauh tidak dibebani dengan sewa tanah atau pajak serupa, harus tunduk pada pajak verponding. Dengan ketentuan tersebut, ada dua alternative bagi pembebanan kewajiban dalam bentuk pajak atau kewajiban lain, yaitu sewa tanah atau pajak verponding. Mengingat sewa tanah (landrent) menurut konotasi lama menunjukkan bahwa pemegang hak tanah bukan pemilik31 tanah, verponding lebih sesuai untuk menegaskan kepemilikan tanah tersebut karena dengan verponding nilai pokok tanah mulai ditetapkan dibandingkan dengan sewa tanah.32 Namun demikian, meskipun ada pembebanan kewajiban yang sah dan pemberian status yang sah, kepada pemegang hak milik tanah masih ada ketentuan pembatasan lain, yang dimuat dalam pasal 19 peraturan ini, yaitu: 31 32 146 Dalam pengertian lama, landrent atau sewa tanah, memuat konotasi bahwa pembayarnya bukan pemilik melainkan penggarap tanah, dan pihak yang menerima pembayaran adalah pemiliknya. Pemahaman ini bertumpu pada konsep yang dianut oleh pemerintah Inggris saat itu bahwa semua tanah adalah milik pemerintah atau raja Inggris, dan mereka yang menggarap berstatus meminjam. Meskipun ada kemiripan dengan prinsip yang berlaku di wilayah raja-raja pribumi khususnya di Jawa (vorstenlanden), perbedaannya terletak pada struktur yang melaksanakannya. Periksa Daniel Welco van Welderenp-Rengers, The failure of a liberal colonial policy: Netherlands East Indies, 1816-1830 (The Hague, 1947, Martinus Nijhoff), halaman 21. Pada mulanya, verponding diterapkan bagi perhitungan pajak lokal karena pemerintah menyadari kesulitan yang akan muncul apabila digunakan untuk seluruh macam pajak yang berkaitan dengan tanah dan langsung mengganti landrent. Dengan verponding, pajak dihitung atas sebagian dari nilai jual tanah dan tentu saja hal ini baru bisa dilakukan apabila ada peluang untuk menegaskan kepemilikan tanah itu secara mutlak dan individu. Periksa Willem Huender, Overzicht van den economischen toestand der Inlandsche bevolking op Java en Mandoera (;s Gravenhage, 1921, Martinus Nijhoff), halaman 183. Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht De ingevolge dit besluit in eigendom verkregen grond mag voor 's hands, op strafe van nietigheid der handeling, niet worden vervreemd aan niet-inlanders. Geen ander zakelijk regt mag daarop worden verleend dan dat van hypotheek. Tanah yang memperoleh status hak milik menurut keputusan ini terutama tidak bisa dialihkan haknya kepada non-pribumi, dengan resiko pembatalan tindakan itu. tidak ada hak paten lain yang bisa diberikan kecuali hak hipotik. Dengan demikian bisa dipahami bahwa mereka yang menerima hak milik (eigendom recht) adalah orang pribumi dan pemerintah menjaga sepenuhnya agar tidak dikuasai oleh non-pribumi. Di samping itu juga ada hak hipotik yang memperkuat status hak milik tanah itu, yang tidak bisa diberikan kepada jenis kepemilikan tanah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hak milik (eigendom) menjadi sangat kuat bagi pemegangnya (eigenaar van het grond), daripada pemegang hak kepemilikan (bezitter). D. Penutup Persoalan kepemilikan tanah di antara penduduk menjadi suatu persoalan rumit yang sering memicu pada terjadinya konflik, individu dan sosial. Di samping nilai ekonomi, kepemilikan tanah identik dengan faktor harga diri dan pada kelompok sosial tertentu juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosiofilosofis. Oleh karena itu sering ditemukan kasus sengketa tanah yang berakhir dengan konflik bahkan tidak jarang mengarah pada konflik massal. Semua konflik dan sengketa yang terjadi praktis bersumber pada ketidakjelasan tentang kepemilikan tanah sebagai obyek. Akan tetapi kejelasan tentang pemilik obyek juga tergantung pada kejelasan dan penegasan pada statusnya, yang tidak terlepas dari sistem pengaturan legal yang berlaku dan valid pada zamannya. Banyak dari lahan yang menjadi obyek sengketa di Indonesia dewasa ini yang bersumber dari ketidakjelasan status, dan lebih buruk lagi, status turun-temurun. Dalam hal ini, penelusuran kembali pada awal kepemilikan tanah sangat diperlukan, dan dengan demikian pendekatan historis akan sangat membantu. Dalam kajian historis, kepemilikan tanah khususnya bagi orang pribumi mengalami perkembangan yang kompleks. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaturan hukum atas tanah, dan berakibat pada perubahan hak dan status kepemilikannya. Penerapan hukum positif yang dilakukan sejak pertengahan abad XIX oleh pemerintah kolonial secara perlahan menggantikan penerapan hukum adat, sehubungan dengan status penguasaan dan kepemilikan tanah. Berbeda dengan sistem politik kolonial yang sering ditandai dengan konflik di antara elite, penggantian hukum positif dari hukum adat berlangsung secara bertahap dan damai. Meskipun ada beberapa konflik yang muncul di sektor agraria selama abad XIX, konflik itu bukan menolak penerapan hukum melainkan pada pelaksanaan di lapangan khususnya terkait dengan eksploitasi lahan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa hukum positif Barat tidak selalu berdampak negative terhadap struktur sosial masyarakat. Meskipun memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda dengan masyarakat, pemerintah Belanda 147 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 telah mengambil langkah positif untuk menegaskan kepemilikan lahan oleh masyarakat pribumi. Dengan menetapkan pembagian hak khususnya hak milik tanah (eigendom), status kepemilikan lahan menjadi jelas dan sah. Pemilik hak (eigenaar) mendapatkan jaminan bukan hanya pada hak atas obyek tanah, melainkan juga perlindungan terhadap perampasan oleh orang asing. Akan tetapi mengingat sistem hukum dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial memiliki jangkauan yang terbatas, sehubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat masa itu, ketentuan yang mengatur hak milik (eigendom) ini tidak diterima secara merata oleh semua warga koloni Hindia Belanda. Sebagian besar bahkan masih terbatas pada pemahaman tentang hak kepemilikan (bezitsrecht) atau bahkan masih terikat dengan aturan adat yang bersumber dari hak penguasaan (beschikkingsrecht) atas tanah. Tentu saja situasi ini menjadi penghambat bagi pelaksanaan kepastian hukum dan penerapan status hak milik mutlak individu, dan justru mengarah pada persoalan barn. Proses perkembangan di bidang politik yang berlangsung sangat pesat, dengan berakhirnya rezim kolonial dan tampilnya pemerintah nasional pada tahun 1945, tidak segera diikuti dengan penyelesaian ketidakjelasan di atas yang berlangsung lambat. Pemerintah Indonesia barn mengambil langkah pertama tahun 1960 dengan mengeluarkan UUPA, yang meskipun dianggap sebagai suatu langkah progresif tetapi juga tidak begitu saja menyelesaikan masalah tersebut. Sampai dewasa ini, masih banyak sengketa lahan yang berkisar pada ketidakjelasan status kepemilikan seperti yang disampaikan di atas. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang intensif, dengan melibatkan berbagai pihak dari disiplin ilmu, oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan penjelasan dan penerangan memadai kepada publik tentang pemahaman hak-hak kepemilikan lahan ini. DAFTAR PUSTAKA Anderson, Benedict. G.O., 2006,Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia, Jakarta, Equinox Publ. Anon, 1866, Regeling der heerendiensten op Java, 's Gravenhage, J.A. de la Vieter. Anon,"De koloniale staatkunde tegenover het Buitenland", dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, tahun 1867, jilid 1 Antlov, Hans, and Sven Cederroth, 2001,Kepemimpinan Jawa, Perintah Alus, Pemerintahan Otoriter, Jakarta, Yayasan Obor. Burger, D.H., 1956, Structural Changes in Javanese Society: the Supravillage Sphere, Cornell, Cornell University Press. Circulaire aan de hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en Madoera, 28 October 1875, dimuat dalam Bijblad no. 2936 Collenbrander, H.T. , 1926, Koloniale Geschiedenis, derde deel:• Nederlandsch Oost Indie sedert 1816, s Gravenhage, Martinus Nijhoff. Deventer, Salomon van, 1866, Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, derde deel, Zalt Bommel, Joh. Noman en Zoon. 148 Antara Bezitsrecht dan Eigendomrecht Doel, H.W. van den, 1996, Het Rijk van Insulinde: Opkomst en Ondergang van een Nederlandse Kolonie, Amsterdam, Promotheus. Dutch East Indies, 1912, Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera, vol. 9, Batavia, Landsdrukkerij. Fasseur, Cornelis, 1992, The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System, Ithaca, Cornell University Press. Heere, W.P., and J.P.S Offerhaus, 1998, International Law in Historical Perspective (The Hague, Kluwer Publ. Huender, Willem, 1921, Overzicht van den economischen toestand der Inlandsche bevolking op Java en Mandoera, ;s Gravenhage, Martinus Nijhoff. Lekkerkerker, C., Land en Volks van Java, vol I., Amsterdam, 1938, J.B. Wolters. Linden, M.L.M. van der, 1907, De gronverhuring door inlanders aan nietinlanders op Java en Madoera: vastgesteld door ordonnantie van 27 Augustus 1900, Rotterdam, Masereeuw en Bouten. Moertono, Soemarsaid, 1985, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Jakarta, Yayasan Obor. Pierson, Nicolaas Gerard, 1868, Het kultuurstelsel: zes voorlezingen, Amsterdam, P.N. van Kampen. Resink, G.J., "Conflictenrecht van de Nederlands-Indische staat in internationaalrechterlijke setting" dalam Bijdrage tot de Koloniaal Instituut (BKI), tahun 1959, jilid 115. Scheuer, Willem Philip, 1885, Het grondbezit in de Germaansche mark en de Javaansche dessa, Rotterdam, Wed. F.G. Mortelmans. Soest, Gerardus Hubertus van, 1871, Geschiedenis van het Kultuurstelsel, vol. 3, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1870, no. 55. Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1872 nomor 66 Staatsblad van Nederlandsch Indie 1872 no. 117 Staatsblad van Nederlangsch Indie over het jaar 1874 no. 78. Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1875 no. 179. Staatsblad van Nederlandsch Indie over het jaar 1885 no. 102 Tadama, Wop van W., 1866, Indische brieven van Mr. Wop over koloniale hervorming : proeven van wets-ontwerpen voor radikale, geleidelijke en konservatieve hervormers, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Tjodronegoro, Sediono M.P., dan Gunawan Wiradi, 2008, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa, Jakarta, Yayasan Obor. Vollenhoven, C. Van, 1923, Javaansch adatrecht: Overgedrukt uit het adatrecht van Nederlandsch Indie, Leiden, E.J. Brill. Vollenhoven, C. van, 1932, Indonesier en zijn grond, Leiden, E.J. Brill. Welderen-Rengers, Daniel Welco van, 1947, The failure of a liberal colonial policy: Netherlands East Indies, 1816-1830, The Hague, Martinus Nijhoff. 149 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Wilson, Stuart, and Singgih Wibisono, 2002„Javanese English Dictionary, Singapore, Periplus. 150 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 BIOGRAFI PENULIS Prof Dr. H. Abdul Latif, SH. M.Hum. Lahir di Ujung Pandang, 25 September 1959, menyelesaikan pendidkan sarjana (S1) Universitas Muslim Makassar tahun 1986, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 1996 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta tahun 2006. selain sebagai dosen beliau juga aktif menulis dibeberapa jurnal ilmiah serta menulis banyak buku tentang ilmu hukum, saat ini menjabat sebagai Hakim Agung, pernah menjadi Dekan fakultas hukum universitas Muslim Makssar dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis dalam pemerintahan. Herlambang Perdana, SH. Lahir Wuluhan, 8 mei 1976, Si Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1998), S2 - Mahidol Univercity, Thailand Kini sedang menempuh Program PhD di Faculteit Rechgeleerdheid, Universteit Leiden. Sejumlah artikel telah diterbitkan baik dalam jurnal nasional maupun intemasional. Penulis buku Good Governance and Legal Reform in Indonesia. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Prof Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., lahir di Pare-pare, tanggal 11 November 1952. Pendidikan berawal dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas ditempuh di tempat kelahiran. Hijrah ke Makassar pada tahun 1973 untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selesai tahun 1980. Kemudian pendidikan Magister di bidang Ilmu Hukum Pajak pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 1997 dan selesai tahun 2000, dan di tingkat Doktoral dalam bidang Ilmu Hukum Pajak pada tahun 2000 dan selesai tahun 2006. Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pajak. Dalam pengembaraannya sebagai Guru Besar di bidang Hukum Pajak, telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku yang bertaraf nasional yang diterbitkan oleh Rajawali Pers, khususnya PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Karya ilmiah tersebut meliputi; 1) Pembaruan Hukum Pajak; 2) Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak; 3) Hukum Keuangan Negara; 4) Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5) Kejahatan di Bidang Perpajakan; dan 6) Hukum Acara peradilan Pajak. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., dilahirkan di Malang pada 5 Oktober 1961. Sejak tahun 1987 hingga sekarang menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UA) pada Prodi Si, S2 dan S3. (NIP. 19611005 198701 2001- Pangkat / Golongan: Lektor Kepala/Pembina/IV-A). Pendidikan S1 (S.H.), diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Magister (M.Hum), pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung dan gelar Doktor Ilmu Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Hukum (Dr), diperoleh dari Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya. Bidang ilmu yang ditekuni dan dikembangkan sesuai dengan studi penulis adalah Hukum Intemasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Teknik Perancangan Perjanjian Internasional, Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Sumberdaya Alam. Selain menjadi dosen di Universitas Airlangga, penulis juga menjadi dosen tamu di Prodi S2 Teknik Kelautan ITS 10 November Surabaya, Prodi Magister Administrasi Publik pada Universitas Hang Tuah Surabaya, dan di Kodikal Armatim Surabaya, serta menjadi narasumber dan pembicara di berbagai seminar dan konferensi baik lingkup nasional dan internasional. Untuk memperdalam bidang keilmuan dan meningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran penulis melakukan penelitian melalui pendanaan dari DIPA UA, Program Hibah Bersaing, dan Riset Unggulan Perguruan Tinggi serta melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, Sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga, penulis juga menjadi bagian dari penyelenggaraan proses pembelajaran, dan aktif sebagai Tim Asesor Sertifikasi Dosen UA, Auditor pada Audit Mutu Internal Program Studi / Fakultas dan Unit Kerja UA; Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT-2010-sekarang); Koordinator PHKI Batch IV Fakultas Hukum Universitas Airlangga; dan Sekretaris pada Pusat Penjaminan Mutu Universitas Airlangga (2011-sekarang). Beberapa kegiatan pada organisasi profesi dan keilmuan, antara lain: menjadi Ketua Asosiasi Pengajar HI (APHI) wilayah Jatim dan Sekretaris APHI Seluruh Indonesia (2007-sekarang); Staf Ahli pada drafting untuk Penyusunan Raperda Prop Jawa Timur ; Anggota Kelompok Studi Perbatasan; Anggota Himpunan Ahli Pengelolaan Perairan Pesisir Indonesia (HAPPI); Forum Pemerhati Terumbu Karang (Forum Hati Terang) Jawa Timur, Anggota, Koordinator Divisi Hukum (2010-sekarang). Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA Jakarta, ditugaskan di Balitbang Diklat Kumdil MA RI, alumnus S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta, Dosen Fakultas Hukum UNBAR JAMBI, Hj. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H., Dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Budi Suharyanto, SH., M.H. lahir di Jombang Jawa Timur, menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekarang adalah Peneliti Bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Harto Juwono, kahir di Magelang 17 Juli 1967, Sarjana sejarah lulusan Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Universitas Diponegoro semarang tahun 1992, lulus Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2006 dan program doctor pada universitas yang sama tahun 2011. Dosen Pasca Sarjana fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, terlibat dalam berbagai penelitian tentang sejarah dan menulisbanyak buku dan artikel ilmiah tentang masalah pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 PEDOMAN PENULISAN JURNAL Jurnal Hukum dan Peradilan adalah media yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, terbit 3 (tiga) kali dalam setahun (Maret, Juli dan November). Jurnal Hukum dan Peradilan menerima sumbangan naskah di bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan: 1. Naskah dikirim dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti hasil penelitian lapangan, analisis/tinjauan putusan lembaga peradilan, kajian teori, studi kepustakaan serta gagasan kritis konseptual yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptis. 2. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana dan mudah difahami dan tidak mengandung makna ganda. 3. Naskah harus orisinil dengan dibuktikan pernyataan akan keorisinilan naskah tersebut oleh penulis. 4. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sepanjang 15-25 halaman. Naskah diketik diatas kertas A4 menggunakan huruf Time New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Naskah harus disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara 100-150 kata. 5. Sistematika penulisan hasil penelitian harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Abstrak (berhasa Indonesia dan bahasa Inggris), Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Hasil penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, daftar Pustaka. 6. Sistematika penulisan analisis putusan, kajian teori, wacana hukum harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Abstrak (berhasa Indonesia dan bahasa Inggris), Pendahuluan, Pembahasan (langsung dibuat sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), Kesimpulan, Daftar Pustaka. 7. Penulisan daftar pustaka secara alfabetis mengikuti Turabian Style dengan tata cara penulisan sebagai berikut: Buku. Weiss, Daniel A. Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence, Seattle: University of Washington Press, 1962. Makalah. Knight, Robin. “Poland‟s Feud in the Family.”, New York, 10 September 1990, 52-53, 56. Artikel Jurnal. Sommer, Robert. “The Personality of Vegetables: Bonatical Metaphors for Human Characteristics.” Journal of Personality 56, no. 4 (December 1988): 665-683. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan. Tillich, Paul. “Being and Love” In Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen, 661-72. New York: Harper & Bros., 1952. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Internet Rost, Nicolas, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl. “A Global risk assessment model for civil wars.” Social Science research 38, no. 4 (December 2009): 921-933. http//www.sciencedirect.com/science/ article/ B6WX84WMM7CY1/2/aa8571448b4774e8831a (accessed October 15, 2009) 8. Daftar pustaka hendaknya dirujuk dari edisi paling mutakhir. 9. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnotes) mengikuti turabian Style dengan tata cara penulisan sebagai berikut: Buku. Daniel A. Weiss, Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence (Seattle: University of Washington Press, 1962), 62. Makalah. Robin Knight, “Poland‟s Feud in the Family.”,U.S. New and Work Report, 10 September 1990, 52. Artikel Jurnal. Robert Sommer, “The Personality of Vegetables: Bonatical Metaphors for Human Characteristics.” Journal of Personality 56, no. 4 (December 1988): 670. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan Paul Tillich, “Being and Love,” in Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen (New York): Harper & Bros., 1952), 663. Internet Nicolas Rost, Gerald Schneider, and Johannes Kleibl, “A global risk assessment model for civil wars,” Social Science Research 38, no.4 (December 2009): 922, http://www.sciencedirect.com/science/B6WX84WM M7CY1/2/aa85435453ae88c432a 10. Naskah kiriman dalam bentuk softcopy atau hardcopy yang dilampiri dengan biodata singkat (CV) penulis, copy NPWP penulis, alamat email, No. telp/hp, naskah dapat dikirim via email ke e-mail redaksi jurnal atau puslitbang kumdil Mahkamah Agung RI 11. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penerbitan kepada: Redaksi Jurnal Mahkamah Agung Gedung Skretariat Mahkamah Agung RI Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat 13011 email: [email protected] atau [email protected] 12. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan diatas tidak akan diseleksi. Dewan editor berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa merubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Redaksi Jurnal Mahkamah Agung. artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan kepada penulis. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 Jurnal Hukum dan Peradilan Menyampaikan terima kasih Kepada para Mitra Bestari (referee) dan semua pihak Yang telah membantu penerbitan jurnal ini Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274 VISI: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional di bidang teknis peradilan dan manajemen kepemimpinan serta hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam membentuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan yang agung MISI: 1. 2. 3. 4. Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia teknis peradilan Meningkatkan kualitas profesionalisme manajemen dan kepemimpinan Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan Meningkatkan pelayanan dan dukungan operasional diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan dan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan yang memadai Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013 ISSN : 2303-3274