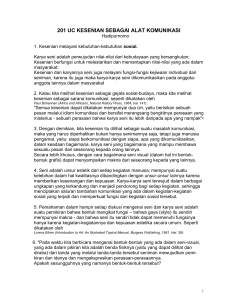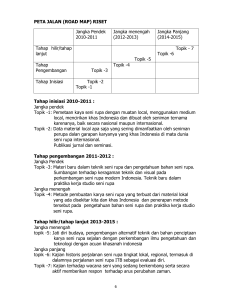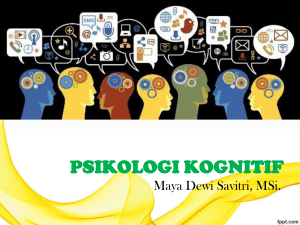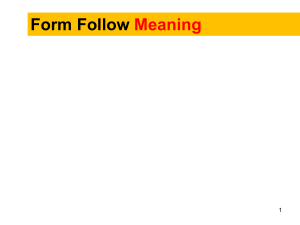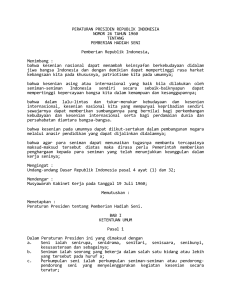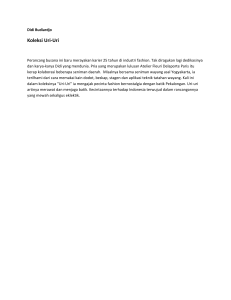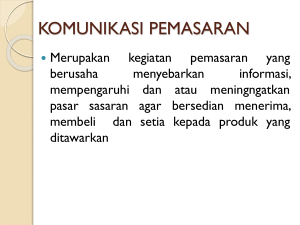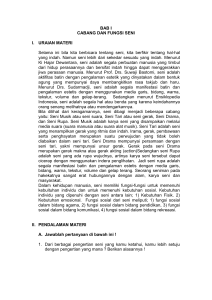seni sebagai ekspresi emosi
advertisement

SENI SEBAGAI EKSPRESI EMOSI (Telaah Hakiki dan Nilai Seni dalam Ekspresivisme) Oleh: Sunarto * Abstrak Hakiki seni merupakan topik perdebatan yang seakan tiada habis dalam estetika atau filsafat seni. Ekspresivime merupakan aliran estetika yang mendefinisikan seni dalam konteks emosi dan perasaan. Hal ini berbeda dengan, aliran representasi yang mendefinisikan seni dalam konteks tiruan realitas dan aliran formal yang mendefinisikan seni dalam konteks struktur karya seni. Penelitian ini bertujuan menunjukkan konsep hakikat seni menurut ekspresivisme, perbandingan antar sub-aliran di dalamnya, kelemahan-kelemahan, dan ide-ide berharganya. Tulisan ini berfokus pada estetika tradisional sebagai objek formal dan pandangan ekspresivisme tentang seni sebagai objek material. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep hakikat dan kualitas seni, sarana seni, kandungan seni, dan audien seni. Hakiki seni menurut ekspresivisme adalah ekspresi emosi. Sub-aliran di dalam ekspresivisme, baik ekspresivisme harian atau ekspresivisme lanjut memiliki beberapa pokok persamaan, perbedaan, dan kelemahan dalam konsep kualitas seni, sarana seni, kandungan seni, dan audien seni. Aliran ini mempunyai andil besar dalam membedakan antara memahami seni secara imajinasi dan konseptual. Kata Kunci : ekspresivisme, hakiki seni, sarana seni, kandungan seni, dan audien seni Pendahuluan Ada satu pandangan yang begitu luas diterima di dunia seni bahwa karya seni merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan dan emosi. Misalnya seseorang menyatakan: “Baitbait musik Indonesia tahun 1980-an ‘melankolis’ dan ‘cengeng’, puisi-puisi Rendra penuh dengan ‘perlawanan’, lagu-lagu perjuangan begitu ‘semangat’, atau lukisan-lukisan Affandi ‘ekspresif’”. Pandangan ini biasanya bertumpu pada asumsi bahwa seniman merupakan seorang jenius yang bisa menggunakan sarana-sarana untuk mengekspresikan perasaan dan emosinya; karya seni dianggap sebagai wujud dari perasaan dan emosi dari sang seniman; dan audien seni merupakan orang-orang yang menikmati karya seni dan tersentuh perasaannya. Sebagai suatu ekspresi perasaan dan emosi seniman, seni merupakan pandangan yang telah lama berkembang dalam wilayah estetika. C.P.E. Bach (dalam Shepard 1987:19) pada tahun 1753 menyatakan, bahwa seniman harus benar-benar bisa menyatukan perasaan dan * Penulis adalah Doktor Filsafat yang menjadi Staf Pengajar Musikologi dan Filsafat di Jurusan Sendratasik, FBS, dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 1 pengalamannya ke dalam karyanya. Menurutnya, seorang musisi hanya bisa menggerakkan orang lain bila dirinya memang memiliki daya yang menggerakkan. Ia harus bisa merasakan semua efek yang diharapkan akan muncul pada audiennya. Eugéne Véron (dalam Davies 2003:169-170) dalam bukunya Aesthetics, pada tahun 1879 juga menegaskan bahwa hakiki seni adalah manifestasi emosi yang diekspresikan melalui serangkaian garis, bentuk atau warna, gerak, suara atau kata yang ditata di dalam suatu irama tertentu. Menurutnya, rangkaian karya seni pada akhirnya harus diukur berdasarkan kekuatan yang mewujudkannya, yaitu emosi. Suatu karya seni disebut indah ketika mampu menggerakkan dan menelusup dengan kuat ke dalam perasaan setiap individu. Dengan menghubungkan seni dengan perasaan dan emosi, seniman sering dinisbatkan sebagai orang yang memiliki tingkat kepekaan perasaan tersendiri yang berbeda dengan orang pada umumnya. Seniman diyakini sebagai pribadi yang memiliki cita rasa yang halus, lembut, dan mudah ‘terjentik’ oleh suatu kenyataan atau pengalaman orang lain dan dirinya sendiri. Dengan berbekal kejeniusan batinnya, seniman menghasilkan karya seni. Pandangan karya seni yang merupakan ekspresi emosi menjadi suatu pokok bahasan yang semakin berkembang dan bercabang dalam ekspresivisme. Tak jauh berbeda dengan Bach dan Véron, aliran estetika ini juga memegangi suatu pendapat bahwa seni berurusan dengan emosi. Tolstoy (1969:65), novelis dan filsuf Rusia, sebagai salah satu tokoh penting ekspresivisme, dengan tegas menyatakan bahwa : Art is a human activity consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others feeling he has lived through, and that other people are infected by these feeling and also experience them. Karya seni dianggap berhasil ketika semakin berhasil membangkitkan emosi audien. The stronger the infection the better is the art, demikian kata Tolstoy. Di samping itu, secara moral ia menyatakan bahwa seni sejati mengkomunikasikan dan membangkitkan sesuatu yang bernilai mulia, dan bukan perasaan-perasaan rendah seperti hasrat seksualitas. Berbeda dengan Leo Tolstoy, Croce (1969:90-91) seorang filsuf Italia, tokoh ekspresivisme yang lain, mengatakan bahwa seni bukan merupakan persoalan moral. Seni pada hakikinya adalah intuisi. Sesuatu yang memungkinkan terjadinya intuisi ini adalah perasaan yang intens. Perasaan yang intens ini bukanlah ide atau gagasan yang bersifat kognitif. Wilayah seni adalah wilayah estetis, sehingga standar yang digunakan adalah apresiasi estetis. 2 Sementara itu, Collingwood (dalam Graham 2003:126) seorang filsuf Inggris dan tokoh ekspresivisme lain, juga menyatakan suatu pandangan bahwa seni terkait dengan emosi sang seniman. Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang seniman adalah mengekspresikan emosi. Ia menyatakan: “the artist’s business is to express emotion; and the only emotion he can express are those which he feel, namely his own…”. Namun demikian, Collingwood berbeda dengan Tolstoy dan Croce. Menurutnya seni tidak berhubungan dengan bagaimana membangkitkan perasaan pada audien. Membangkitkan emosi audien merupakan tujuan utilitarian, dan bukan hakiki seni itu sendiri. Di samping itu, tujuan akhir suatu karya seni bukan hanya apresiasi estetis, tetapi lebih merupakan sejenis introspeksi yaitu “pengetahuan diri” (self-knowledge). Seniman dan audiennya secara bersama-sama sampai pada suatu pengetahuan diri sehingga bisa melihat dunia dalam cakrawala yang baru dan lebih luas. Melihat beragam penjelasan seputar konsep seni sebagai emosi menjadi menarik karena masih banyak kalangan yang berpendapat demikian, bahwa seni senantiasa berhubungan dengan rasa dan emosi. Di samping itu, ternyata ada beragam penjelasan yang berbeda bagaimana hubungan seni dan emosi tersebut harus dijelaskan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana ekspresivisme menjelaskan hakiki seni?, mengapa terjadi perbedaan di antara penyokong ekspresivisme?, dan apa kelemahan-kelemahan pandangan mereka? Untuk membahas konsep seni dalam ekspresivisme ini, penulis menggunakan estetika tradisional sebagai objek formal atau kerangka pembahasan. Estetika tradisional merupakan estetika yang hendak meneropong karya seni dari hakiki dan nilainya (periksa Graham 1997:149155). Hakiki dan nilai tersebut mencakupi dimensi kualitas seni, kandungan seni, sarana seni, dan audien seni. Ekspresivisme Harian Tolstoy (1969) hendak menjelaskan hakiki seni dalam dua konteks, yakni teori estetika dan etika. Dengan teori estetika, ia ingin menunjukkan kapan sesuatu layak disebut sebagai seni atau tidak. Dengan teori moral, ia berusaha menunjukkan kapan suatu seni disebut baik dan buruk. Bagi Tolstoy, banyak orang melihat seni dengan cara yang tidak akurat, yakni melihat objekobjek seni demi tujuan kenikmatan (pleasure) dan tidak melihatnya dalam kerangka hidup dan kemanusiaan. 3 Dalam pandangan Tolstoy seni mengandung dua pengertian yaitu seni merupakan komunikasi emosi dan seni harus bermoral. Aktivitas seni, menurutnya, semacam aktivitas ‘bahasa’ yang menyatukan manusia dalam ‘emosi’ (lihat Stolnitz, 1960:173-174). Setelah merasakan suatu emosi, seniman harus menggunakan sarana-sarana eksternal, seperti gerakan, garis, warna, suara, atau kata-kata untuk mentransmisikan perasaannya sehingga orang lain bisa memahaminya. Bila seseorang mengkomunikasikan gagasan (thought) melalui kata-kata atau percakapan biasa maka seseorang mengkomunikasikan perasaan (feeling) melalui seni. Dalam bernalar orang menggunakan bahasa logika, dalam merasa orang menggunakan bahasa seni. Komunikasi gagasan dianggap berhasil ketika orang lain memahaminya, sementara komunikasi perasaan dianggap berhasil ketika orang lain bisa merasakan perasaan tersebut (Tolstoy 1969). Dalam pemikiran Tolstoy, seni bukan hanya menjadi bahasa universal secara ontologis tetapi sekaligus menjadi bahasa moral, karena dengan seni manusia menjadi lebih beradab dan santun. Tanpa seni manusia menjadi keras, kaku, dan liar. Menjadi beradab berarti manusia memiliki kehendak untuk bisa menyapa dan berdialog dengan orang lain, menjadi liar berarti manusia akan tertutup dan tidak menaruh perhatian pada yang lain. Dalam pemikiran Tolstoy (dalam Davies 1975:169-170), istilah seni sebagai alat komunikasi mengandung dua unsur, yakni: ungkapan (expression) dan kemerasukan (infection). Ekspresi merupakan proses di mana apa yang berada dalam dunia subjektif seniman, yaitu perasaannya, menjadi mewujud dalam bentuk-bentuk yang bisa diakses orang lain. Kemerasukan merupakan proses di mana ekspresi seniman diasimilasi oleh orang lain. Apa yang diekspresikan seniman dan dipahami oleh audien adalah perasaan dan bukan gagasan. Kedua proses ini mengandaikan bahwa apa yang subjektif di dalam dunia batin seniman menjadi objektif milik publik. Dalam mengekspresikan emosi, seorang seniman tidak mengekspresikan apa yang dirasakannya secara langsung, melainkan menggunakan sarana-sarana eksternal, seperti nada, suara, gerak, kata-kata, dan warna. Dengan mengekspresikan melalui sarana-sarana eksternal itu, seseorang berharap orang lain menjadi tersusupi atau terasuki atau terpengaruh (infected) oleh apa yang dirasakan seniman (Tolstoy 1969). Sesuatu yang dikomunikasikan, menurut Tolstoy, adalah perasaan (feeling) atau emosi (emotion). Perasaan merupakan sesuatu yang hendak diekspresikan oleh seniman dan perasaan 4 juga merupakan sesuatu yang hendak dipahami oleh audien dalam suatu karya seni. Perasaan tersebut bisa sangat kuat atau sangat lemah, sangat penting atau sangat remeh, sangat buruk dan sangat baik seperti cinta tanah air, kesetiaan, dan persaudaraan. Tolstoy (1969) menetapkan 3 (tiga) standar sebagai ukuran bahwa suatu seni akan berhasil untuk merasuki audien, yaitu: (1) individualitas (individuality); (2) kejelasan (clearness); dan (3) ketulusan (sincerity). Semakin kuat individualitas karya seni, akan semakin kuat dalam berpengaruh pada audien. Semakin individual suatu karya seni, semakin audien menikmati dan semakin kuat ia terlibat. Semakin jelas suatu ekspresi maka akan sangat membantu mempengaruhi audien, karena audien akan semakin bisa menangkap apa yang dimaksudkan seniman yang hanya ditangkap dari ekspresinya. Seorang seniman mengekspresikan emosi atau perasaanya bukanlah bernyanyi, menulis, atau bermain peran untuk dirinya sendiri, melainkan semua itu dilakukan demi kepuasan penonton, pembaca, atau pendengar. Tanpa ketulusan, audien akan cenderung menolaknya, sehingga akan gagal proses komunikasi perasaan. Di antara ketiga ukuran tersebut yang paling penting adalah ketulusan. Ketulusan merupakan kondisi yang harus ada bagi individualitas dan kejelasan. Seniman yang tulus, batinnya akan terdorong untuk mengekspresikan perasaannya dengan penuh kejujuran, sebagaimana halnya ia mengalami demikian, dan bukan sebaliknya. Perasaan yang diekspresikannya akan sangat individual dan berbeda dengan cara orang lain dalam mengekspresikannya. Semakin tulus, seorang seniman akan semakin bisa menemukan cara yang jelas dan jernih untuk mengekspresikan perasaannya. Tolstoy menggunakan tiga kriteria tersebut untuk membedakan seni sejati dan seni palsu (counterfeits). Tiadanya ketiga kriteria ini akan membuat suatu seni menjadi seni palsu. Dengan kata lain, jika suatu karya tidak diekspresikan dengan individualitas, tidak diekspresikan dengan jelas, dan bukan merupakan dorongan nyata dari dalam batin seniman, maka hal itu bukan karya seni. Ketiga kriteria ini bisa tampil dalam cara yang kombinatif. Selanjutmya Tolstoy membedakan antara seni yang baik dan yang buruk. Dari sudut estetis, seni yang baik harus menyenangkan setiap orang untuk mengaksesnya, dan dari sudut moral, seni bisa menyatukan manusia dalam suatu moralitas relijius. Secara estetis, seni yang baik harus memenuhi tiga kondisi. Pertama, suatu seni harus dapat diakses oleh audien tanpa bantuan interpretasi yang dilakukan oleh kritisi seni. Kedua, respon audien terhadap seni tidak bergantung pada tingkat pendidikannya. Suatu seni tidak terikat dengan suatu kelas tertentu. 5 Ketiga, seni yang baik adalah ketulusan (sincerity). Dengan didorong dari dalam batinnya, seorang seniman kemudian mengekspresikan emosi ini. Dorongan emosi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang diharap, bukan pula sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang menggelora dan mendorong seniman untuk membuat ekspresi-ekspresi (Tolstoy 1969: 62). Seni yang sesungguhnya harus mengandung perasaan moral dan agama. Seni yang baik adalah seni yang mentransimisikan kenikmatan dan persatuan spiritual. Dengan standar moral, maka tak mengherankan bila Tolstoy kurang menghargai dan menganggap rendah karya seni yang mengekspresikan kebanggaan, seksualitas, nafsu, dan tidak memiliki nilai kehidupan. Sementara itu, ia lebih menempatkan karya seni yang mengekspresikan persaudaraan dan spiritualitas sebagai superior (periksa Gaut 2003: 341-343). Kandungan dari suatu karya seni, menurut Tolstoy, adalah ‘persepsi relijius’ (religious perception), yakni ide tentang kebapaan Tuhan dan persaudaraan manusia. Menurutnya, setiap periode sejarah dan di setiap masyarakat selalu ada pemahaman tentang makna hidup. Makna hidup ini merepresentasikan tingkat pemahaman paling tinggi yang bisa diraih manusia yaitu tentang kebaikan. Lebih lanjut, persepsi relijius ini biasanya diekspresikan oleh suatu generasi sebelumnya dan diterima masyarakat secara umum (Tolstoy 1969: 68). Ekspresivisme Lanjut Ekspresivisme menjadi lebih ketat dan sistematis secara filosofis di tangan dua tokoh pentingnya, yakni filsuf kebangsaan Italia Benedetto Croce (1866-1952) dan filsuf kebangsaan Inggris R.G. Collingwood (1889-1943). Menurut Graham (2003:129), ekspresivisme di tangan dua tokoh tersebut menjadi lebih filosofis dan menjadi salah satu prestasi yang sangat besar pada abad ke-20. Bagi Croce, seni tak bukan dan tak lain adalah intuisi. Menurutnya, seorang seniman menciptakan suatu image atau fantasi, sedangkan seseorang yang menikmati seni tersebut mengarahkan pandangannya pada suatu titik hakiki yang ditunjukkan oleh seniman, melihat melalui celah yang dibukakan oleh seniman dan kemudian mereproduksi atau mencipta-ulang di dalam dirinya. 6 Menurut Croce (1962:88-93) seni bukan fakta fisik, bukan untuk tujuan kenikmatan, moralitas dan intelektual. Croce menegaskan bahwa seni bukan merupakan fakta fisik, seperti warna, relasi warna, suara, relasi suara, gerak tubuh sampai dengan fenomena elektrik. Musik berbeda dengan nada-nada yang tersusun, lukisan berbeda dengan cat atau kanvas, dan puisi berbeda dengan kata-kata tersusun. Dalam pandangan Croce, definisi yang melihat seni sebagai fakta fisik harus ditolak berdasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah fakta fisik tidak memiliki realitas, sementara seni memiliki realitas-utama (supremely real). Bahkan menurutnya seorang ahli fisika yang selalu bergulat dengan benda-benda fisik setiap hari tahu bahwa benda fisik bukanlah kenyataan yang ada pada dirinya sendiri, di sana selalu ada prinsip yang disebut dengan ‘konstruksi intelektual’. Mengkonstruksi seni secara fisik juga tidak berguna. Sebagai contoh seseorang bisa saja memilah-milah suatu puisi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil baik dalam bentuk kata dan huruf. Tindakan ini mungkin dan absah dilakukan, sebagaimana memang banyak terjadi. Orang membuat topografi, pengukuran, atau pemilihan dalam berbagai bentuk, tetapi semua tindakan itu justru menjauhkan orang dari makna dan hakiki seni (Croce 1962:89). Di samping itu, seni bukanlah aksi utilitarian. Suatu tindakan utilitarian selalu berusaha mencapai kenikmatan. Seni tidak berhubungan dengan kegunaan, kenikmatan, kesenangan. Dicontohkan, kenikmatan meminum air yang mendinginkan tenggorokan, berjalan di udara terbuka sehingga membuat sirkulasi darah lebih lancar, bukanlah seni walaupun mendatangkan kenikmatan. Melihat seni sebagai tindakan utilitarian harus ditolak karena: (a) tindakan utilitarian selalu bertujuan meraih kenikmatan dan menjauhkan seni dari hakikinya, yakni tidak berhubungan dengan kegunaan dan kenikmatan; (b) kenikmatan sebagai kenikmatan bukanlah suatu tindakan artistik, seperti minuman penyegar atau minuman keras adalah menikmatkan tetapi bukan seni; dan (c) keindahan sebagai suatu kenikmatan bisa saja pada suatu ketika, sebagai contoh kasus, memori kita yang indah dan menyenangkan digambarkan secara buruk atau sebaliknya suatu lukisan yang indah tetapi merepresentasikan hati yang sakit sehingga bisa membuat seseorang menjadi marah. Lebih lanjut, seni bukanlah suatu tindakan moral. Kelompok yang mengedepankan moral di dalam seni biasanya melihat bahwa kekuatan spiritual harus menjadi superior di dalam seni, lebih utama dibanding kenikmatan hedonis dan utilitarian. Seni memang paling sering dikaitkan 7 dengan persoalan moral. Sebagai misal di kalangan seniman tradisional wayang juga sering muncul jargon, bahwa wayang bukan hanya ‘tontonan’ tetapi juga ‘tuntunan’. Wayang bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan bimbingan moral. Namun demikian, menurut Croce, seni dan moral memiliki wilayah yang berbeda. Seni tidak ditujukan untuk menyenangnyenangkan audien secara moral. Terakhir, seni bukanlah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual, menurut Croce, selalu memiliki karakter menegaskan atau mengunggulkan kenyataan (reality) terhadap yang tidak-nyata (unreality). Yang tidak nyata selalu diposisikan sebagai subordinate terhadap yang nyata. Sementara itu seni sebagai intuisi tidak membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Intuisi merupakan image sebagai image, tanpa predikat (Croce 1962:92). Menurut Croce pengetahuan terdiri dari dua jenis, yaitu pengetahuan intuitif dan pengetahuan logis. Atau dalam istilah lain, antara pengetahuan yang diperoleh melalui imajinasi dan pengetahuan yang diperoleh melalui intelek. Pengetahuan intuisi merupakan pengetahuan tentang yang individual, sementara pengetahuan logis merupakan pengetahuan tentang yang universal (Croce 1962:97). Pengetahuan konseptual termasuk di dalamnya filsafat, sejarah, sains, membedakan antara yang nyata dan tidak nyata , dan memiliki pengandaian tentang suatu ‘dunia yang berada di sana’. Sebaliknya, intuisi tidak membedakan keduanya. Pengetahuan intuisi berstatus sebagai idea image murni, yaitu seni atau karya seni. Untuk memahami karya seni seseorang cukup hanya dengan menyaksikannya, dan bisa tidak menghiraukan ‘dunia sana’. Pada prinsipnya, seni adalah nonlogis (Graham 2001:121). Berbeda Croce, berbeda juga dengan Collingwood. Terdapat 4 (empat) definisi yang menurut Collingwood keliru dalam melihat seni, yakni seni sebagai kerajinan (craft), seni sebagai representasi (representation), seni sebagai magis (magic), dan seni sebagai hiburan (amusement) (Graham 2001:123). Bagi Collingwood, seni bukan kerajinan karena dalam seni tidak dibedakan antara sarana dan tujuan, rencana dan penyelesaian. Kedua aspek tersebut membentuk kesatuan dan tidak ada saat jeda. Ia mengatakan, expression is an activity of which there can be no technique… (Graham 2001:23). Menurutnya, di dalam seni tidak dibedakan antara sarana dan tujuan. Dengan mereduksi menjadi sarana, seniman jatuh pada posisi sebagai pengrajin, yaitu mengabdi pada 8 suatu tujuan untuk mempengaruhi audien. The artist is not a purveyor of drugs, kata Collingwood. Seniman bukanlah penyetor cita rasa. Di samping itu, seni juga bukan representasi atau cerminan kenyataan. Representasi merupakan persoalan teknik atau skill, sementara seniman tidak bisa membayangkan suatu hasil sebelum menyelesaikannya. Seorang seniman, secara literal tidak tahu kandungan ekspresi karya seninya sebelum diekspresikan. Seorang seniman yang mencoba untuk merepresentasikan emosi yang bergelora di dalam batinnya, jatuh menjadi seorang pengrajin karena di dalamnya terpilah antara rencana dan penyelesaian. Seniman mengekspresikan dan bukan merepresentasikan. Collingwood juga membedakan seni magis dan seni sejati. Seni magis adalah representasi emosi yang memiliki nilai guna dan diritualkan demi tujuan-tujuan praktis, bukan untuk tujuan katarsis. Sebagai misal tarian perang, tarian untuk mengundang hujan, atau tarian dalam pesta pernikahan. Menurut Collingwood seni juga bukan sebagai hiburan. Dalam seni sebagai hiburan, seni berfungsi sebagai sarana untuk merangsang emosi dan menggerakkannya. Sebagai contoh, drama, film atau musik ditujukan untuk menggerakkan emosi audien. Namun demikian, hiburan bukanlah seni, tetapi kerajinan, demikian Collingwood. Seniman yang sibuk dengan urusan membangkitkan emosi sebenarnya bukanlah seniman melainkan pengrajin. Menurut Collingwood, seni adalah ekspresi emosi, dan kedua, seni adalah imajinasi emosi. Collingwood menggambarkan suatu kondisi yang menurutnya biasa dialami oleh seorang seniman. Seorang seniman biasanya merasa ada sesuatu yang ‘mengganjal’ dan ‘mengganggu’ dalam batinnya. Namun demikian, seniman tidak tahu persis apa yang dirasakan tersebut. Perasaan ini begitu menekan, sehingga ia harus mengekspresikannya. Setelah diekspresikan ia menjadi tenang dan cerah, dan baru tahu apa yang dirasakan selama ini (Graham, 2003:124125). Seni sejati, menurut Collingwood, terdiri dari dua unsur, yaitu ekspresi dan imajinasi. Seniman semula merasakan emosi yang ‘mengganggu’ di dalam batinnya, namun demikian ketika seniman harus mengekspresikan, maka imajinasi memegang peran. Collingwood menolak pendapat bahwa emosi itu telah jelas dan eksis sebelumnya di dalam pikiran, karena emosi itu samar. Ia hendak mengatakan bahwa antara merasakan emosi dan menciptakan karya seni 9 merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan. Yang menyatukan adalah peran imajinasi. Melalui konstruksi imajinasi, seniman mentransformasikan emosi yang samar dan tidak jelas ke dalam artikulasi ekspresi. Proses ini, bagi Collingwood, juga bukan proses menggunakan sarana-sarana eksternal untuk mengekspresikan emosi yang dialami oleh seorang seniman, karena proses ini merupakan proses imajinatif. Pada satu sisi, memang urusan seniman hanyalah mengekspresikan emosi yang mengganjal pikirannya, sebagaimana dikatakan oleh Collingwood bahwa the artist’s business is to express emotions; and the only emotion he can express are those which he feels, namely his own…. Namun demikian, pada sisi lain, proses ini bukan proses egois sebagai kerja personal seniman, karena apa yang dirasakan oleh seniman juga milik publik atau sesuatu yang juga dirasakan oleh publik, sebagaimana juga dikatakan: “in other words he undertakes his artistik labour as a personal effort on is own private behalf, but as a public labour on behalf of the community to which he belongs” (Graham 2003:127). Dengan kata lain, emosi ini merupakan perasaan bersama. Emosi ini lebih mirip harta benda publik, namun hanya seniman yang bisa mengekspresikannya secara imajinatif. Sebagai konsekuensinya, posisi audien tidak ditempatkan sebagai peserta pasif di dalam apresasi karya seni, sebagaimana seniman juga aktif dalam kreasi karya seni. Jika ekspresi emosi merupakan proses imajinatif, maka apresiasi yang harus dilakukan oleh audien juga harus imajinatif, karena audien harus menciptakan ulang apa yang ada dalam batin seniman ke dalam benaknya sendiri. Proses memahami karya seni tidak terjadi secara lahiriah tetapi secara batiniah. Proses ini merupakan proses penemuan secara imajinatif. Tujuan puncak proses ekspresi dan apresiasi adalah penemuan diri (self discovery), yakni pengenalan diri baik bagi seniman atau pun audien. Bagi seniman, dengan imajinasi perlahan-lahan ia mengenali emosi di dalam batinnya dan ketika diekspresikan menjadikan terkenali wujud karya seni yang sebenarnya. Sementara itu bagi audien, dengan imajinasi audien berusaha memahami karya seni yang memang imajinatif, bila berhasil maka audien bisa sampai pada apa yang dialami seniman di dalam batinnya (Graham 2003:125). 10 Konklusi dan Kritik Konklusi yang bisa diambil mengenai hakiki seni menurut ekspresivisme adalah ekspresi emosi seniman. Ekspresivisme harian menekankan bangkitnya emosi audien sebagai ukuran baik dan buruknya seni dan ekspresivisme lanjut menekankan independensi aktivitas seni dari tujuan utilitarian. Ekspresivisme harian berpandangan bahwa emosi yang dirasakan seniman jelas dan eksis sebelumnya di dalam pikiran atau batin seniman, sementara pada ekspresivisme lanjut, emosi tersebut samar dan belum jelas, dan akan menjadi jelas setelah selesai diekspresikan secara imajinatif. Pada ekspresivisme harian menunjukkan perlunya sarana eksternal sebagai bagian dari hakiki karya seni, sementara ekspresivisme lanjut memposisikan sarana eksternal sebagai sekunder, karena hakiki seni ada di dalam pikiran bukan pada benda fisik. Ekspresivisme harian memposisikan audien secara pasif, sementara ekspresivisme lanjut memposisikan audien secara aktif. Pandangan-pandangan tersebut dalam perspektif tertentu memiliki kelemahan. Secara umum, ekspresivisme mereduksi hakiki seni pada asal usulnya. Sebagaimana diketahui, Tolstoy mengasalkan seni pada emosi, Croce mengasalkan pada ‘perasaan yang mendalam’, dan Collingwood mengasalkan pada emosi ‘yang mengganjal’ dan ‘mengganggu’. Dengan kata lain, seniman-seniman seperti Shakespeare, Beethoven, Affandi, Iwan Fals, dianggap memiliki emosi tertentu dan kemudian diekspresikan. Pendapat ini merupakan salah satu bentuk generalisasi empiris dan merupakan ‘kesalahan genetik’ (genetic fallacy). Tidak semua karya seni melibatkan emosi dalam batin, sebagai contoh misalnya arsitek dengan karya arsitektur bangunannya. Apakah suatu bangunan bisa disebut merupakan ekspresi perasaan sedih, gembira atau bahagia? Beberapa seniman terkenal justru sering menolak bahwa ada emosi dalam batinnya ketika menciptakan karya seni (Matravers 2003:353). Di samping itu, menurut Hospers (dalam Matravers 2003:353-354), menghubungkan karya seni dengan ‘perasaan yang mendalam’ atau emosi yang mengganggu, mengabaikan perbedaan antara karya seni yang sederhana dan karya seni yang kompleks. Sangat mungkin seseorang menemui lagu yang dianggap sebagai ekspresi suatu rasa gembira, tetapi orang juga tak jarang berhadapan dengan karya seni yang kompleks dengan berbagai jenis perasaan, misalnya novel Linus Suharyadi, Pengakuan Pariyem, yang bisa mengekspresikan duka dan derita seorang 11 Pariyem, tetapi juga merupakan ekspresi kebahagiaan Pariyem untuk memegangi suatu keyakinan, dan banyak ekspresi yang lain. Lebih lanjut, juga akan sulit untuk menemukan kriteria untuk menetapkan jenis emosi pada suatu karya yang kompleks bila ada dua audien yang berbeda dalam menangkapnya, siapa yang paling tepat hasil tangkapannya. Secara lebih khusus, dari sudut kualitas seni, bila keberhasilan karya seni diukur dari seberapa besar dan banyak mempengaruhi orang, maka hal itu menjadi janggal. Bila pendapat tersebut diikuti dengan konsisten, maka akan banyak karya seni justru gugur statusnya sebagai karya seni, atau paling dekat dianggap sebagai seni yang buruk karena tidak atau kurang berhasil mempengaruhi audien. Contohnya sebuah pamflet justru lebih sering bisa membangkitkan emosi audien dibandingkan puisi, atau lukisan realistis lebih mempunyai daya magnet dibanding lukisan ekspresionistis. Bahkan bila bangkitnya emosi dijadikan standar, maka tak dipungkiri lagi musik rock akan menempati posisi tertinggi dalam keunggulan karya seni karena memiliki massa yang lebih banyak dibanding musik klasiknya: Beethoven, Bach, Kitaro atau musik kroncong dan jazz. Juga film-film horor dan drama percintaan akan memiliki nilai lebih tinggi dibanding film-film spiritual atau film-film kearifan lokal (Shepard 1987:21). Dari sudut sarana seni, ekspresivisme lanjut juga lemah karena menempatkan sarana eksternal hanya sebagai sekunder di dalam ekspresi emosi untuk menjadi suatu karya seni, sebab karya seni ada di dalam pikiran seniman dan tidak terletak pada benda-benda fisik. Jika pandangan ini diikuti dengan konsisten, maka akan banyak karya seni justru kehilangan statusnya sebagai karya seni. Di dalam beberapa genre seni, ada persinggungan antara kreativitas, pada satu sisi, dan bentuk serta prosedur sebagai teknik, pada sisi lain. Sebagai contoh sederhana, seorang pelukis pemula akan belajar tentang bentuk-bentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga dan tentang teknik-teknik menggunakan kuas, cat, kanvas, dan kombinasi warna. Seorang musisi pemula juga harus belajar berbagai bentuk dan jenis musik, belajar notasi nada, melodi, dan alat-alat musik. Semakin menguasai hal-hal teknis dan praktis yang berhubungan dengan suatu bidang seni, seorang seniman akan lebih mudah mengekspresikan emosinya ke dalam genre seni tertentu. Dari sudut kandungan seni, menempatkan emosi sebagai kandungan karya seni bukannya tanpa kesulitan. Mungkin saja suatu ketika seniman menciptakan suatu karya seni dengan penuh emosi dan audien mengapresiasinya juga dengan penuh perasaan. Namun di dalam kenyataan, seorang seniman mungkin mengalami rasa bosan dan ia hanya mengulang-ulang karya yang 12 pernah dibikinnya, dan tentu saja karya seni yang sedang ia ekspresikan tidak memiliki kandungan rasa bosan, ekspresinya tetap seperti sebelum ia merasa bosan. Bila ini yang terjadi maka emosi tidak lagi terdapat pada batin seniman, tetapi terdapat pada karya seni tersebut. Terakhir dari sudut posisi audien, ekspresivisme menepiskan peran audien sebagai subjek yang menyejarah. Audien bukan subjek yang netral dan tidak terikat dengan pengalaman hidupnya. Setiap audien selalu membawa konteksnya ketika harus memahami karya seni. Dengan kata lain, ekspresivisme menyimpan suatu objektivisme epistemologis, bahwa subjek sesungguhnya netral terhadap objek yang sedang dihadapinya. Ketika standar tertinggi dalam apresiasi seni ditempatkan dalam keberhasilan memasuki ruang batin pengarang, maka peran subjek interpretasi karya seni menjadi surut. Audien harus menanggalkan konteks sejarahnya, dan ini merupakan suatu proses yang mustahil. Bila meminjam pemikiran Gadamer, seorang interpreter telah selalu berada di dalam ‘tradisi’ tertentu. Tradisi tersebut bisa berupa latar sosial, budaya, atau pengetahuan. Setiap subjek yang mendatangi karya seni senantiasa memiliki horizon kesejarahan dan bila horizon yang dimiliki bertemu dan melebur dengan horizon yang melingkupi suatu karya seni, maka terjadilah pemahaman atau interpretasi. Dengan mengabaikan horizon audien, ekspresivisme menjadi a-historis, psikologis dan objektivis. Pertanyaannya adalah mungkinkah suatu pemahaman terhadap suatu karya seni terjadi di dalam ruang yang vakum dan steril. Benarkah ada subjek yang benar-benar kosong dan netral? Daftar Pustaka Collingwood, R.G. 1938. Principles of Art. Oxford: Clarendon Press. Croce, B. 1962. Guide to Aesthetics,. New York: Bobbs-Merrill. Davies, S. “Definition of Art”, in Gaut, B. and McIver Lopes. 2003. Hal. 169-179. Gaut, B. and McIver Lopes. 2003. The Routledge Companion to Aesthetics. London and New York: Roetledge Gaut, Berys. “Art and Ethics”, in Berys Gaut, B. and McIver Lopes. 2003. Hal. 341-352. Graham, G. “Expressivism Croce and Collingwood”, in Gaut, B. and McIver Lopes. 2003. Hal. 120-122. 13 Graham, G. 2001. Philosphy of the Art: An Intoduction to Aesthetics. London: Routledge. Matravers, D. “Art, Expression and Emotion”, in Gaut, B. and McIver Lopes. 2003. Hal. 353-362. Sheppard. 1987. Man in the Landscape: A History View of the Esthetics of Nature. New York: Knopt. Stolnitz, J. 1960. Aesthettics and Philosophy of Art Criticism. New York: Houghton Mifflin. Tolstoy, L. 1969. What is Art. Oxford: Oxford University Press. 14