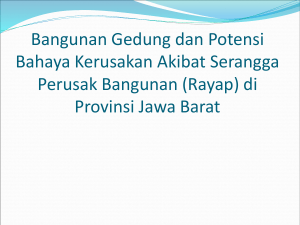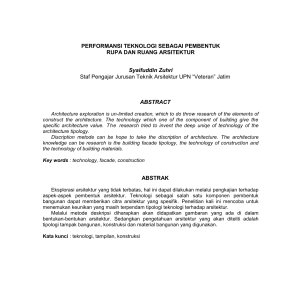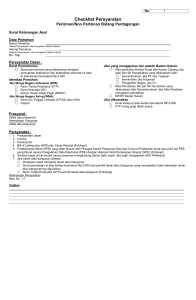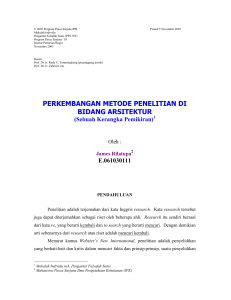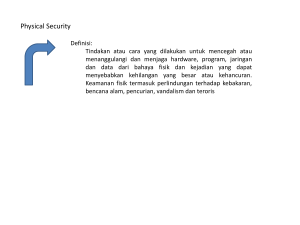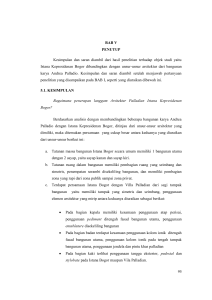Ketidak-panggahan dalam Arsitektur Kajian - Repository
advertisement

Disertasi Ketidak-panggahan dalam Arsitektur Kajian tentang Arsitektur Kramat Buyut Trusmi REVIANTO BUDI SANTOSA 3213301004 DOSEN PEMBIMBING Prof. Dr. Ir. Josef Prijotomo, M.Arch. Dr. Ir. Murni Rachmawati, MT PROGRAM DOKTOR BIDANG KEAHLIAN ARSITEKTUR JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2016 i LEMBAR PENGESAHAN Disertasi disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (Dr) di Institut Teknologi Sepuluh November oleh REVIANTO BUDI SANTOSA NRP. 321 3301 004 Tanggal Ujian Periode Wisuda : 1 Februari 2017 : 115 Prof. Dr. Ir. Josef Prijotomo, M.Arch. NIP 19480312197703 1 001 ......................... (Pembimbing I) Dr. Ir. Murni Rachmawati, MT NIP 19620608 198701 2 001 ......................... (Pembimbing II) Ir. Purwanita Setijanti, M.Sc. Ph.D NIP 19590427 198503 2 001 ......................... (Penguji) Prof. Dr. Ir. Sekartedjo, M.Sc. NIP 19500402 197901 1 001 ......................... (Penguji) Dr. Ir. Yuswadi Saliya, M.Arch. NIP 2007 0183 ......................... (Penguji) a.n. Direktur Program Pascasarjana, Asisten Direktur Prof. Dr. Ir. Tri Widjaja, M.Eng . NIP. 19611021 198603 1 001 ii KATA PENGANTAR Arsitektur Nusantara adalah wilayah kajian yang terbentang luas. Sementara banyak pengkaji menggunakan pendekatan sejarah untuk mendalami arsitektur di berbagai wilayah Nusantara, saya mencoba untuk mengkajinya dengan mengembangkan teori arsitektur. Di satu sisi, dalam wacana teori arus utama (manistream) arsitektur dipandang sebagai produk yang purna dan dicipta untuk abadi. Di sisi lain, banyak praktik berarsitektur di Nusantara yang justru memosisikan arsitektur sebagai proses dengan menekankan pada aspek kesementaraan. Kajian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara keduanya dengan menelaah arsitektur Kramat Buyut Trusmi di Kabupaten Cirebon yang memiliki tradisi untuk memperbarui bangunan secara terus menerus. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Josef Prijotomo, M.Arch. selaku pembimbing utama yang memberikan tantangan kepada penulis untuk merambah wilayah ini dengan membuka wawasan baru. Ucap terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Murni Rahmawati, MT selaku pembimbing kedua dengan cermat, teliti dan sabar membimbing penulis untuk menyusun kajian yang dpat dipertanggungjawabakan secara ilmiah. Kepada para penguji, Prof. Dr. Ir. Sekartedjo, M.Sc., Ir. Purwanita Setijanti, M.Sc. Ph.D dan Dr. Ir. Yuswadi Saliya, M.Arch., penulis menyampaikan terima kasih untuk masukan-masukan kritis yang disampaikan dalam evaluasi maupun konsultasi yang berperan penting dalam mengarahkan dan meningkatkan kualitas kajian. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terimakasih kepada para pembimbing atas semua kritik, saran, wawasan dan masukan dari para pembimbing dan penguji sambil tetap bertanggung jawab atas semua kekurangan dalam kajian ini. Disertasi ini dapat disusun dan studi dapat ditempuh atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII, Ketua Program Studi Arsitektur UII atas dukungan penuh untuk dapat menempuh studi. 2. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November ( ITS), Direktur Program Pasca Sarjana ITS, Ketua Jurusan Arsitektur dan Ketua Program Studi Pascasarjana, para dosen di Jurusan Arsitektur ITS atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk menjalani studi pada Program Doktor dan memberi masukan ilmu pengetahuan secara rutin pada perkuliahan dan seminar rutin dalam masa studi di ITS. 3. Sekretariat program Studi Pasca Sarjana Arsitektur, Laboratorium Komputer dan Perpustakanan Jurusan Arsitektur ITS yang telah memberi pelayanan selama masa studi. iii 4. Rekan-rekan peserta S3 Program Studi Pasca Sarjana Arsitektur ITS yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka dalam menempuh studi saling memberi masukan serta kritikan dan motivasi sehingga sampai penyelesaian naskah disertasi. 5. Seluruh teman-teman dosen Program Studi Arsitektur FTSP UII yang selalu memberi kesempatan dan motivasi, khususnya kepada adinda Dr. Yulianto P. Prihatmaji yang memotivasi dan mendampingi selama observasi lapangan. 6. Warga Desa Trusmi Kulon dan Trusmi Wetan, para pengelola Kramat khusunya Kiai Tony dan Kunci Harto yang memberi kesempatan pada penulis untuk terlibat dalam berbagai peristiwa di Kramat. 7. Kiai Warlan sekeluarga yang setulus hati menerima penulis dan tim sebagai keluarga dan memberikan sangat banyak wawasan dan kesempatan untuk mendalami masyarakat dan lingkungan Trusmi. Bagi penulis, studi ini adalah upaya dan kesibukan bersama yang melibatkan seluruh keluarga besar. Tanpa dukungan mereka sulit membayangkan untuk dapat menempuh dan menyelesaikan studi ini. Setulus hati ucap terima kasih saya sampaikan, semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi semua. Ayahnda Zamharir Sangidhu, Ibunda Sumarni Zain yang senantiasa berdoa. Kesabaran, dukungan dan keceriaan Ita Dian Novita istri tercinta, ananda Safitri “Cinta” Alia Dzikrina dan Ali “Boboiboy” Ardhya Maulana telah menghidupkan hari-hari indah selama studi. Dengan sabar dan asyik adinda Nur Asriyah dan Rahmat Taufiq Syamsuri, serta keponakan Afifah Nurul Falih mendampingi penulis dan keluarga selama studi. Kesempatan studi dan mengkaji adalah suatu kenikmatan. “Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang kamu dustakan”. Syukur dan puji kami persembahkan, kepada Allah semata sembari mohonkan setitik berkah dan hikmah dari samudera ilmu-Mu ya Rabb. Surabaya. 1 Februari 2017 Penulis Revianto Budi Santosa iv DAFTAR ISI Lembar Pengesahan ii Kata Pengantar iii Daftar Isi v Daftar Gambar vii Abstrak ix BAB I: PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang: Mengidealisasikan Keabadian dan Merengkuh Kesementaraan 2 1.2. Tradisi Arsitektur Tak-Permanen di Nusantara 6 1.3. Mengkaji Arsitektur Tak-Permanen di Trusmi 11 1.4. Arsitektur dan Sifat Tak-Panggah: Beberapa Definisi Operasional 14 1.5. Teori Arsitektur di Antara Kepanggahan dan Ketak-panggahan 15 1.6. Permasalahan 28 1.7. Tujuan dan Manfaat 33 BAB II: KAJIAN PUSTAKA 35 2.1 Teori Tentang Sistem Arsitektur dan Aspek Ke[Tidak]Panggahan 35 2.2 Ketidak-Panggahan dalam Kajian Arsitektur Nusantara 53 2.3 Landasan Teori: Klassen dan Norberg-Schulz 57 BAB III: METODA KAJIAN 79 3.1 Karakteristik Objek: Ketidak-panggahan dalam Arsitektur Kramat Buyut Trusmi 80 3.2 Karakteristik Teori: Klassen dan Norberg-Schulz 81 3.3 Strategi Penelitian Kualitatif 82 3.4 Pendekatan: Fenomenologi dan Hermeneutika 84 3.5 Metoda Kajian 87 3.6 Kerangka Kajian 90 3.7 Kerangka Penulisan 93 v BAB IV: MEMBANGUN ARSITEKTUR, TEMPAT DAN RELASI DI KRAMAT BUYUT TRUSMI 95 4.1. Pengantar 95 4.2. Ingatan Kolektif yang Terpenggal 96 4.3. Membangun Tempat, Menjalin Relasi 98 4.4. Pelaku, Hubungan Sosial Dan Aktivitas Mereka 107 4.5. Tektonika: Bentuk, Konstruksi Dan Ornamentasi Bangunan 110 4.6. Buka Sirap 123 4.7. Memayu 137 4.8. Pemugaran dan Pengembangan Bangunan Tak-Berkala 149 4.9. Beberapa Temuan 162 BAB V: MENAFSIR MAKNA MENJADI KONSEP-KONSEP DASAR 165 5.1. Konsep Tempat 166 5.2. Konsep Waktu 173 5.3. Konsep Material 179 5.4. Konsep Konstruksi 186 BAB VI: MENGEMBANGKAN TEORI ARSITEKTUR DENGAN KETIDAK-PANGGAHAN 194 6.1 Relasi dalam Berarsitektur dengan Ketidakpanggahan 196 6.2 Relasi dalam Berarsitektur dengan Ketidakpanggahan 202 6.3 Diskusi Komparasi Teori: Ketidak-panggahan di antara yang terurai dan yang tak stabil 212 BAB VII: SIMPULAN DAN SARAN 223 6.4 Ketak-panggahan untuk Hadirkan Asal Muasal 223 6.5 Process dan PresenceArsitektur yang Hidup 226 6.6 Saran untuk Kajian Berikutnya 229 REFERENSI 229 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Lukisan “The Architect’s Dream” 3 Gambar 1.2. Bagian utama World’s Columbian Expo di Chicago 5 Gambar 1.3. Pagelaran Kraton Surakarta pada awal abad ke-20 8 Gambar 1.4. Menara pembakaran jenazah Puri Klungkung 9 Gambar 1.5. Bale Malang di Desa Gamel 10 Gambar 1.6. Pemasangan atap alang-alang di Trusmi 12 Gambar 1.7. “Plug in City”, Peter Cook 25 Gambar 1.8. Model “City in the Air” yang diajukan Arata Isozaki 28 Gambar 1.9. Atap Masjid Kramat Buyut Trusmi seusai Buka Sirap 33 Gambar 2.1. Rumah Batak Toba dengan elemen tangga dan vegetasi 56 Gambar 3.1. Wawancara dengan Sep Tony 90 Gambar 3.2. Kerangka Kajian 92 Gambar 4.1. Kompleks Kramat Buyut Trusmi 99 Gambar 4.2. Kelompok bangunan di sekitar gapura timur 101 Gambar 4.3. Kelompok bangunan di sekitar Kabuyutan 101 Gambar 4.4. Kelompok bangunan di sekitar Gapura barat 102 Gambar 4.5. Kenduri di Paseban usai Buka Sirap 104 Gambar 4.6. Pola pengembangan permukiman Trusmi 106 Gambar 4.7. Gapura timur 112 Gambar 4.8. Bentuk bangunan dan struktur saka guru Witana 113 Gambar 4.9. Bangunan Kabuyutan dan Pendopo 115 Gambar 4.10. Bale Pasalinan dan Batu Pendadaran 117 Gambar 4.11. Ruang dalam bangunan utama Masjid 118 Gambar 4.12. Masjid dan serambi yang beratap sirap dan Pawadonan yang beratap alang-alang 119 Gambar 4.13. Paseban, Bale Kiai dan Bale Kunci 121 Gambar 4.14. Struktur utama Paseban 121 Gambar 4.15. Bale Kiai dengan atap terbuka saat Memayu 122 vii Gambar 4.16. Sirap dalam berbagai ukuran 124 Gambar 4.17. Menyucikan sirap dan komponen konstruksi di Balong Pakulahan di samping Witana 125 Gambar 4.18. Para pengobeng dan tukang menunggu Buka Sirap dimulai 125 Gambar 4.19. Melepas bubungan Kabuyutan dan meletakkannya di atas kabel baja yang ditopang perancah kayu Gambar 4.20. 127 Para pengobeng berebut menyentuh dan membawa keluar bubungan jurai yang telah diturunkan 128 Gambar 4.21. Memasang sirap baru di sisi selatan atap Kabuyutan 129 Gambar 4.22. Penurunan mustaka Masjid yang disunggi Lebe` 130 Gambar 4.23. Menurunkan sirap dan bubungan jurai sisi timur Masjid 131 Gambar 4.24. Mengganti atap sisi timur Witana 131 Gambar 4.25. Kiai Warlan menyeleksi sirap baru untuk Kabuyutan 133 Gambar 4.26. Memasang kembali bubungan atap Kabuyutan 135 Gambar 4.27. Modin menyerukan adhan di puncak Masjid 136 Gambar 4.28. Bagian ritualistik Parade Ider-ideran 140 Gambar 4.29. Menurunkan welit dengan rangken dari Bale Kunci 143 Gambar 4.30. Pelepasan welit tanpa rangken dari Bale Keprinci 144 Gambar 4.31. Membuat bubungan welit 145 Gambar 4.32. Pemasangan welit pada rangken di Jinem 146 Gambar 4.33. Pemasangan rangken di Jinem Wetan 146 Gambar 4.34. Dugaan pengembangan awal Kramat Buyut Trusmi 154 Gambar 4.35. Peta Permukiman dan Kramat Buyut Trusmi tahun 1926 156 Gambar 4.36. Angka tahun yang tertera pada berbagai bangunan 158 Gambar 4.37. Angka tahun di konsol gapura dalam makam 159 Gambar 4.38. Gapura dalam Makam yang diubah penutup atapnya menjadi sirap 163 Gambar 6.1. Ragam simpul dalam tradisi Jepang 215 Gambar 6.2. Altar bambu dengan hiasan dedaunan 217 viii KETIDAK-PANGGAHAN DALAM ARSITEKTUR Kajian Tentang Arsitektur Kramat Buyut Trusmi Nama Mahasiswa NRP Pembimbing I Pembimbing II : Revianto B. Santosa : 3213301004 : Prof.Dr.Ir. Josef Prijotomo, MArch : Dr. Ir. Murni Rachmawati, MT ABSTRAK Dalam teori arsitektur yang berkembang, terutama di Eropa dan Amerika, arsitektur diasumsikan sebagai produk yang final dan permanen sehingga diupayakan untuk berada sebagaimana kondisi pada akhir penciptaan. Pada kenyataannya arsitektur berubah baik karena faktor-faktor alami atau karena faktor-faktor keterlibatan manusia. Di Nusantara banyak praktik berarsitektur yang bukan hanya menerima adanya perubahan tapi bahkan merayakannya sehingga menciptakan arsitektur yang memang tidak abadi, yang disiapkan untuk diubah, yang terus menerus diperbaiki atau bahkan yang ditujukan untuk dihancurkan. Kesenjangan yang besar antara praktik yang menegaskan ketidak-panggahan dan teori yang didasari atas prinsip kepanggahan tersebut menjadi fokus kajian ini melalui pengembangan teori dasar arsitektur yang menekankan pada arsitektur sebagai proses dan observasi terhadap tradisi arsitektur yang menekankan pada ketidak-panggahan. Teori yang terpilih adalah teori Klassen (1990) tentang “The Process of Architecture” dan teori Norberg-Schulz (2000) tentang “The Presence of Architecture”. Objek yang dikaji adalah Kramat Buyut Trusmi di Cirebon yang memiliki tradisi pembangunan berulang dengan material tak-panggah dalam skala besar, melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak serta berakar pada budaya setempat dalam jangka waktu yang lama. Dengan menggunakan metoda fenomenologi-hermeneutika sebagaimana kedua teori yang dikembangkan tersebut, kajian ini diharapkan mampu untuk menyajikan gambaran serba cakup tentang objek yang dikaji dan mengembangkan masingmasing komponen teori maupun keseluruhannya. Pengamatan secara fenomenologis dilakukan terhadap tradisi Memayu (mengganti atap alang-alang) yang diselenggarakan tiap tahun, Buka Sirap (mengganti atap sirap kayu jati) yang diselenggarakan tiap empat tahun, serta pembangunan tak berkala di Kramat Buyut Trusmi. Dari pendalaman terhadap tradisi tersebut dengan pendekatan hermeneutika didapatkan sejumlah konsep kunci yang melandasi praktik berarsitektur dengan ketidak-panggahan yang menonjol di Trusmi. Konsep tentang tempat yang menjadi asal muasal sekaligus bertransformasi menjadikan pembangunan berkala penting untuk menghidupkan kembali momen awal, sedangkan pembangunan tak berkala ditujukan untuk mentransformasikan kompleks ini. Konsep tentang ix waktu yang bersifat sinkronis dan diakronis yang untuk memahami alam dan kehidupan sosialbudaya di Trusmi menjadi landasan konstruksi temporal pelaksanaan pembangunan. Konsep tentang material memberikan gambaran tentang sifat-sifat masing-masing material dan kesesuaiannya untuk tiap bagian bangunan. Konsep tentang konstruksi dipahami sebagai upaya memperbaiki, mengembangkan tapi juga mengembalikan keseluruhan kompleks ke peristiwa asalnya. Rumusan konseptual tersebut menjadi masukan untuk mengembangkan kedua teori arsitektur tersebut. Secara keseluruhan kajian ini mengembangkan teori Heidegger tentang kediaman Empat Serangkai yang dirujuk oleh Klassen dan Norberg-Schulz. Kediaman yang didasari pada relasi antara bumi, langit, manusia dan tuhan ini selalu dihidupkan dan diintensifkan dalam tradisi membangun tersebut sehingga menjadi praktik yang bermakna. Berdasar konsep-konsep tersebut, masing-masing komponen teori dikembangkan dengan menekankan pada ketidak-pangahan sebagai berikut: 1) “Mewujudkan arsitektur” sebagai proses berulang yang melebur batas antara pembuatan dan penggunaan arsitektur, serta antara pembuat dan pengguna arsitektur; 2) “Memanfaatkan arsitektur” yang meliputi manfaat fisik, sosial dan spritual termasuk di dalamnya pembangunan sebagai strategi pemanfaatan; serta 3) “Menghayati arsitektur” yang meliputi penghayatan fisik, intelektual dan spiritual yang diperoleh melalui praktik menciptakan dan memanfaatkan arsitektur serta menjembatani kedua praktik tersebut. Kata kunci: teori arsitektur Klassen dan Norberg-Schulz, Kramat Buyut Trusmi, Memayu, arsitektur tak-panggah, material yang mudah lapuk, pembaruan bangunan berkala. x IMPERMANENCE IN ARCHITECTURE Study on the Architecture of Buyut Trusmi Shrine Name ID number Promotor Co-Promotor : Revianto B. Santosa : 3213301004 : Prof.Dr.Ir. Josef Prijotomo, MArch : Dr. Ir. Murni Rachmawati, MT ABSTRACT Architectural theories, especially those in Western Europe and North America, are developed with the assumption that architecture is a final and permanent object. All effort after its cosntruction is to keep the architecture in a pristine state. In reality, architecture change due to natural factors and human factors. In Indonesia many practices related with architecture which accept and even celebrate changes. People create architecture which are ephemeral, ready to change, perpetually renewed or intended for its annihilation. The main focus of this research is to fill the gap between practices celebrating the ephemerality of architecture and theories emphasizing on the permanence of architecture. To overcome the gap, an in-depth observation on Buyut Trusmi Shrine in Cirebon is carried out. This place has a tradion to renew its building periodically using perishable materials in a large scale, involving thousands of participants, and deeply rooted in the local custom for centuries. The result of this observation is employed to develop Klassen’s (1990) theory on “The Process of Architecture” and Norberg-Schulz (2000) theory on “The Presence of Architecture”; both see architecture as a process rather than a final product. Applying phenomenology and hermeneutics methods as in both theories above, this research is carried out to provide a comprehensive view before focusing on the renewal of some buildings in this place. This phenomenological observation focus on the Memayu (thatch roof renewal), Buka Sirap (shingle roof renewal) and non-periodic construction in Kramat Buyut Trusmi. Hermeneutic interpretation is performed to discover the underlying cultural concepts of building remewal tradition employing perishable materials. These concepts are: 1) Place, emphasizing on its role as the site of origin and its transformation, 2) Time, intertwining diachronic and synchronic views, 3) Materials, related with its nature and its appropriate use, and 4) Construction as an effort to renew and return to origin. Overall, these concepts are relevant with Heidegger’s notion of Fourfold Dwelling relating a meaningful existence of a place with earth, sky, divine and mortals. These patterns of relations is enlivened and preserved in building renewal practice tradition in Trusmi. Based on these concepts of the development of the two theories above are formulated as a new trilogy, namely: 1) “Creating architecture” as repetitive process and involving a large number of people blurring the boundary between making and using and between makers and xi users, 2) “Taking benefit of architecture” including physical, social and spiritual benefits, which includes the process of construction itself, and 3) “Comprehension of architecture” including physical, intellectual and spiritual comprehension bridging the experience in making and using architecture. Keywords: architectural theories of Klassen and Norberg-Schulz; Buyut Trusmi Shrine; impermanence architecture; perishable materials; periodic building renewal. xii BAB 1 PENDAHULUAN Arsitektur, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut sebagai bangunan, dibuat dengan melibatkan upaya dan sumberdaya yang besar dan jangka waktu yang relatif lama dibandingkan dengan benda-benda lain buatan manusia. Bebatuan, misalnya, diangkut dari sungai atau lereng gunung, untuk kemudian dipecah sehingga dapat ditumpuk menjadi landasan yang kokoh. Tanah liat dicetak, untuk kemudian dibakar sehingga menjadi batu bata yang siap dirangkai menjadi pembatas. Pepohonan ditebang, untuk kemudian kayunya dipotong dan diketam sehingga menjadi komponen-komponen beraturan yang disusun sebagai rangka. Dengan upaya yang luar biasa tersebut, bangunan yang dihasilkan diharapkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terlebih jika bangunan yang dibuat memang ditujukan untuk menjadi bangunan monumental, yang menyandang makna mendalam—yang diharapkan dapat diwariskan ke generasi berikutnya—lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan praktik semata. Meskipun manusia adalah makhluk yang fana yang hidup di dunia yang serba sementara, mereka mengharapkan bangunan ciptaan mereka dapat lestari lebih lama dari keberadaan mereka di dunia, atau secara ideal adalah abadi. Teori-teori Arsitektur pun dirumuskan untuk membangun argumen tentang status ontologis arsitektur sebagai yang ciptaan abadi, cara-cara untuk mencapai keabadian, hingga kemanfaatan dari keabadian bangunan. Perhatian utama kajian ini adalah kesenjangan antara teori arsitektur dan praktik arsitektur. Teori arsitektur, khususnya yang dikembangkan di Eropa dan Amerika, didasari pada asumsi bahwa arsitektur ideal adalah objek yang dicipta secara paripurna sehingga dapat bertahan selamanya. Sementara, berbagai praktik 13 berarsitektur, khususnya di Nusantara, bukan hanya menerima sifat ketidakpermanenan arsitektur tapi menjadikan sifat tersebut sebagai bagian inheren dari realitas arsitektur. Kajian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan mendalami praktik berarsitektur yang khas di suatu tempat yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Praktik ini bukan hanya melibatkan sifat ketidakpermanenan tapi bahkan menjadikannya sebagai ungkapan yang menonjol baik dalam wujud fisik bangunan dan lingkungan di tempat tersebut. Tempat yang menjadi lokus bagi kajian ini adalah Kramat Buyut Trusmi, salah satu kompleks peziarahan yang sangat populer dikunjungi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Kramat atau tempat peziarahan ini diyakini sudah ada sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Di tempat ini dilakukan praktik memperbarui atap bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang relatif tak awet yakni alang-alang dan kayu jati secara berkala yang melibatkan khalayak pendukung yang luas. Kajian komprehensif tentang tempat, bangunan dan arsitektur di Kramat Buyut Trusmi diharapkan dapat dipergunakan mengembangkan teori arsitektur tertentu sehingga dapat menjadi lebih inklusif. Untuk dapat memosisikan ketidakpermanenan dalam arsitektur, teori arsitektur yang dipilih adalah yang memaparkan arsitektur dari berbagai aspeknya secara keseluruhan. Dalam paparan komprehensif ini sifat tak permanen dapat dipahami peran dan relevansinya dalam kaitannya dengan totalitas arsitektur tersebut. 1.1. Latar Belakang: Mengidealisasikan Keabadian dan Merengkuh Kesementaraan Lukisan karya Thomas Cole dari tahun 1840 yang bertajuk “The Architect’s Dream” yang saat ini menjadi koleksi The Toledo Museum of Arts terpajang di halaman depan dan membuka wacana sejarah arsitektur dalam buku Kostof (1985:2) A History of Architecture: Setting and Ritual. Dalam lukisan tersebut ditampilkan seorang laki-laki, yakni sang arsitek, yang setengah berbaring di atas kolom pualam 14 raksasa. Di depan sosok arsitek ini tergelar panorama dengan kuil Yunani berlanggam Ionia, kuil Romawi yang berdenah lingkaran serupa dengan Kuil Vesta di tengah kota Roma dan akuaduk Romawi berkonstruksi busur berjajar kokoh terbentang di belakang monumen bundar tersebut. Bangunan dengan atap datar ditopang kolomkolom masif berkepala papirus menyerupai Kuil Ramses di Luxor menyembul di depan Piramida agung, monumen kubur firaun Mesir, yang menjadi latar belakang keseluruhan komposisi akbar ini. Di latar depan sosok gereja berlanggam Abad Pertengahan membayangi dalam wujud siluet menara-menara runcing berseling kaca diafan dengan pohon-pohon cemara di kri kanannya. Mimpi seorang arsitek yang digambarkan dalam lukisan Cole ini adalah mimpi tentang bangunan-bangunan monumental yang menjadi jejak abadi peradabanperadaban terkemuka di dunia. Semua monumen yang membayangi arsitek hingga ke alam mimpi itu terbuat dari batu yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, bertahan melintas jaman dan tangguh lebih dari seribu tahun. Karena keabadian itu semua monumen bisa digelar di latar yang sama dalam mimpi sang arsitek, seolah selang waktu sekitar 3.500 tahun antara gereja Gothik dan Piramida Mesir tak lagi penting. Gambar 1.1. Lukisan “The Architect’s Dream” karya Thomas Cole koleksi The Toledo Museum of Arts (foto: commons.wikimedia.com) 15 Tampaknya Cole ingin mengungkapkan bahwa mimpi ini bukan sembarang khayalan lepas kendali tapi didasarkan pada rujukan tekstual yang sahih. Buku-buku tebal dan besar yang menjadi alas tidur Sang Arsitek menyiratkan pesan bahwa mimpi itu hadir dalam imaji sang arsitek setelah dia mendalami referensi tersebut. Referensi tersebut mungkin merupakan risalah teori dan sejarah arsitektur atau mungkin buku panduan merancang monumen sebagaimana lazim dijumpai di kalangan Akademia Eropa di abak ke-18 dan ke-19 yang menyampaikan doktrin pada sang arsitek tentang arsitektur unggulan yang kokoh dan kekal tersebut. Gambaran ideal tentang keabadian arsitektur ini memicu para arsitek khususnya di dunia Barat untuk membuat bangunan yang seolah-olah akan bertahan seribu tahun. Keawetan atau keabadian diidealkan meskipun lapuk dan lekang adalah realitas tak terbantahkan dalam keberadaan setiap bangunan. Obsesi tentang gambaran monumen yang abadi meskipun menggunakan bahan yang tak awet mengemuka ketika pada pertengahan abad ke-19 tak lama setelah lukisan Cole diproduksi. Saat itu, Amerika Serikat memutuskan untuk menyelenggarakan pameran akbar dengan judul World’s Columbian Expostion. Ekspo ini diselenggarakan di tepi Danau Michigan di Chicago untuk merayakan 400 tahun kehadiran Christopher Colombus di Benua Harapan.Tiga arsitek terkemuka di negri ini, Burnham, Roots dan Olmsted, merancang masterplan Ekspo kelas dunia ini (Scott, 1971: 47). Dengan pameran ini, Chicago mendapatkan kesempatan untuk menampilkan diri sebagai kota kelas dunia sebagaimana laiknya kota-kota utama di Eropa. Panitia penyelenggara Ekspo ini menetapkan untuk membuat suatu kompleks dengan ungkapan monumentalitas, keagungan dan keabadian dengan langgam arsitektur yang telah dikembangkan di Eropa. Ketika Eropa dalam Ekspo serupa di Paris dan London sekitar setengah abad sebelumnya ingin menampilkan perubahan, Amerika justru ingin menonjolkan keabadian pada bangunan-bangunan di dalam Pameran Akbar tersebut. 16 Gambar 1.2. Bagian utama World’s Columbian Expo di Chicago tahun 1893 (foto: colombus.iit.edu) Bangunan-bangunan sangat besar dengan langgam Neo-Klasikpun didirikan di Chicago untuk menegaskan akar perdaban Klasik Yunani-Romawi di negri Amerika. Suatu kompleks dengan langgam yang ditumbuhkembangkan di Eropa dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Gedung Pameran untuk Manufacture and Liberal Arts misalnya adalah bangunan terbesar yang pernah didirikan di dunia saat itu dengan luasan tiga kali lipat Basilika Santo Petrus di Vatikan. Dibuat dengan keteraturan geometris yang ketat, semua bangunan di arena Ekspo ini memiliki corniche atau pelipit atas dengan ketinggian yang sama dengan penampilan serupa pualam berwarna putih lembut yang agung melampaui semua yang pernah didirikan oleh para kaisar Romawi (Junyk, 2013). Hamparan kompleks impian dengan ungkapan monumental yang mampu mewujudkan keabadian yang tergelar di sini pada kenyataannya dibangun dengan serat jute atau goni bercampur semen yang diplester untuk mengefisienkan biaya dan 17 waktu pembangunan. Bangunan-bangunan pualam semu yang agung itu dalam jangka waktu yang tak lama akan lapuk dan lekang. Impian keabadian akan segera berakhir seusai Ekspo. Kompleks yang teramat luas ini, tak dapat dipungkiri, setahap demi setahap, akan menjadi hamparan puing. Kenyataan bahwa bangunan yang memesona dan menjanjikan keabadian itu ternyata hanyalah konstruksi yang bersifat sementara sangatlah mencekam. Charles McKim, salah satu arsitek penting dalam Ekspo tersebut bahkan mengusulkan untuk memusnahkan keseluruhan kompleks ini dalam waktu sekejap dengan menggunakan dinamit. Sebagaimana kehadirannya yang tibatiba, kepergian bangunan-bangunan dengan arsitektur akbar ini haruslah serta merta (Larson 2003 dikutip dalam Junyk, 2013: 7). Arsitektur monumental didirikan untuk melembagakan dan mewariskan makna yang mendalam, dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, bangunan monumental selayaknya memiliki dimensi keabadian untuk mampu tak berubah berabad-abad. Baik Piramid Khufu di Giza, maupun Candi Borobudur di Magelang dibangun dengan menumpuk batu sebagai ungkapan upaya manusia untuk menciptakan bangunan yang menyandang makna mendalam. Monumen-monumen tersebut diyakini mampu bertahan melinasi waktu yang sangat panjang, jauh melampaui masa hidup mereka yang mendirikannya. 1.2. Tradisi Arsitektur Tak-Permanen di Nusantara Banyak catatan menunjukkan sisi lain dari arsitekur yang langgeng tersebut. Mendirikan dan memindahkan bangunan dengan cepat tampaknya menjadi bagian dari tradisi yang berkembang di Asia Tenggara sejak lama. Anthony Reid (1992: 73) mencatat ketakjuban sejumlah pengamat Eropa pada abad ke-17 menyaksikan dua puluh rumah di Makassar dipindah penghuninya, tiga ratus rumah dibangun di Ayutthaya dalam waktu dua hari dan satu kawasan di Banten bahkan dibangun kembali dalam waktu tiga atau empat jam. Suatu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun 1746 memberikan gambaran yang penting tentang pentingnya bangunan-bangunan yang tak permanen 18 dalam khasanah arsitektur Jawa, bahkan untuk sebuah istana. Saat itu, Sunan Pakubuwana II sedang membangun ibu kota Mataram yang baru di Desa Sala, menggantikan Kartasura yang telah porak poranda karena peperangan. Babad Giyanti gubahan Ngabehi Yasadipura yang diterjemahkan dan dikaji oleh Ricklefs (1971) mengisahkan secara rinci kepindahan ini. Sebagaimana lazimnya perarakan seorang raja dalam tradisi Jawa, kirab atau parade kepindahan ke Sala yang disemarakkan dengan kereta, gajah, kuda dan bunyibunyian. Hal yang istimewa dalam parade ini adalah benda yang dibawa. sekarang dikisahkan, tata cara perjalanan, keberangkatan Baginda Raja, terdepan bibit beringin kurung penanda ibukota, yang dibawa dari Kartasura. Berikutnya menyusul Bangsal Pangrawit, diusung utuh diapit pasukan, gajah diapit pawangnya (Ricklefs, 1971: 101) Kalaulah Kraton digagaskan sebagai pengejawantahan semesta, maka di dalam parade tersebut beberapa keping semesta—pars pro toto—yang berupa pohon beringin dan bangsal, dipindahkan dari kedudukannya yang lama yang tak lagi mampu membawa kejayaan untuk dikukuhkan kembali di tempat baru. Kraton yang biasanya dipandang sebagai pusat yang statis dan mapan, di saat krisis harus bergerak dan berpindah untuk menginisiasi konstelasi baru yang akan memulihkan tatanan yang menghantarkan pada kemuliaan. Raja dan warga bergerak bersama dengan Bangsal yang dipanggul dan diarak menuju ke tanah harapan di Sala. Sesampainya di calon istana baru, Bangsal Pangrawit dipasang, di Tarub Pagelaran yang sudah dirakit, segenap pasukan menghadap dengan tertib (Ricklefs, 1971: 102) Bangsal yang diusung ternyata diletakkan ke dalam struktur baru yang sudah dibangun di Sala, yakni Tarub Pagelaran. Yasadipura menggunakan istilah ingetrap atau dipasang untuk Bangsal Pengrawit mengingat pavilyun ini diusung utuh dan rinakit atau dirakit untuk Pagelaran mengingat bangunan ini adalah Tarub atau 19 bangunan semi-permanen atau bahkan sejumlah bagiannya memang tak-permanen. Tak seperti bangunan istana di pelbagai bangsa khususnya Eropa yang memiliki ungkapan monumental paling menonjol di bagian depannya, kraton Jawa justru memiliki bangunan terdepan yang walaupun sangat besar tapi sangat bersahaja dengan naungan anyaman dedaunan yang tak terlalu rapat. Hampir dua ratus tahun setelah Tarub Pagelaran dirakit, bangunan di bagian muka Istana ini tak banyak berubah. Mengenang kunjungannya pada dasawarsa pertama abad ke-20, Zimmerman (2003: 122) menulis tentang kondisi Pagelaran Kraton Surakarta yang menurutnya tak layak karena berupa bangunan seadanya yang beratap daun palem saja, “I remembered that the Pagelaran was not raised above ground level and was furnished only with a sort of thatched roof (atap) which admitted both the sunshine and the rain and seemed shabby.” Gambar 1.3. Pagelaran Kraton Surakarta pada awal abad ke-20 yang masih beratap dedaunan meski sudah bertiang pasangan bata saat perayaan Garebeg (foto koleksi Koniklijk Instituut Tropen Museum) 20 Banyak daerah di Nusantara hingga sekarang yang masih memiliki tradisi yang hidup dengan bangunan yang tak permanen. Bangunan ini memiliki sifat tak permanen lantaran bisa dipindahkan, bisa diganti dan dirakit secara parsial atau terbuat dari bahan yang memang mudah lapuk. Keberadaan bangunan ini bisa bersifat sesaat, khususnya bangunan-bangunan tak permanen yang didirikan untuk keperluan upacara. Beberapa wilayah bahkan memiliki tradisi untuk melebur bangunan secara dramatis dan seremonial seperti menara tinggi yang dibakar habis pada saat upacara Palebon atau Ngaben seorang ningrat tinggi di Bali. Untuk upacara Ngaben di Puri Klungkung yang diselenggarakan pada bulan Mei 2014, misalnya, dibangun menara menjulang yang terbuat dari kayu, bambu dan ijuk bersusun sebelas. Diperlukan waktu lebih dari lima bulan dengan ratusan pekerja dan pengrajin untuk mewujudkan bangunan ini. Dalam waktu yang singkat bangunan tinggi itupun lebur menjadi abu saat perabuan jenazah dilaksanakan. Gambar 1.4. Menara pembakaran jenazah atau bade untuk meperabukan istri Raja Klungkung yang sedang dibangun di depan Puri Klungkung (foto oleh penulis, 2014). 21 Selain itu, ada juga yang keberadaan bangunannya bertahan dalam jangka waktu yang lama namun komponen-komponen penyusunnya senantiasa diperbarui. Tratag Pagelaran di Kraton Yogyakarta dan Surakarta tersebut, misalnya, yang memiliki atap dari anyaman daun namun dapat mempertahan keberadaannya selama lebih dari satu setengah abad. Di antara wilayah yang banyak memiliki tradisi pembangunan ulang secara terus menerus adalah Cirebon. Sejumlah desa di Cirebon memiliki bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah lapuk seperti kayu, bambu dan ilalang yang memerlukan penggantian terus menerus. Bangunan-bangunan di Kramat Seh Magelung, Bale Gede Bangbangan dan Bale Malang di Desa Gamel memiliki atap ilalang yang diganti secara seremonial. Sementara, Makam Ki Gede Kaliwulu dan beratap sirap yang juga diganti secara berkala dengan upacara tertentu. Gambar 1.5. Bale Malang di Desa Gamel yang terletak di depan makam Ki Gede Gamel beberapa hari setelah penggantian atap ilalang dalam upacara tahunan (foto oleh penulis, 2014). 22 1.3. Mengkaji Tradisi Arsitektur Tak-Permanen di Trusmi Kramat Buyut Trusmi adalah kompleks peziarahan di antara sekitar 300-an tempat peziarahan di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam hal luasan lahan dan jumlah peziarah, kompleks yang terletak sekitar 5 kilometer dari pusat Kota Cirebon ini adalah yang terbesar setelah Astana Gunung Jati yang dibangun di Bukit Sembung tempat Sunan Gunung Jati, satu-satunya dari Wali Sanga di Jawa Barat, serta Sultan dan kerabat terdekat Kasultanan Kasepuhan dan Kasultanan Kanoman Cirebon dimakamkan (Muhaimin, 1996: 17). Peziarahan di Kramat ini berfokus pada makam Ki Buyut Trusmi yang terletak di bangunan makam atau sering disebut masyarakat setempat sebagai Kabuyutan yang terletak di dalam bangunan besar di sudut timur laut. Masyarakat setempat meyakini Ki Buyut Trusmi sebagai cikal bakal Desa Trusmi dan bahkan sebagian besar juga percaya kalau tokoh ini adalah putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pra-Islam Pajajaran sekaligus pendiri dan cikal bakal Kota Cirebon dan Kasultanan Cirebon. Mereka juga meyakini bahwa Kramat ini semula adalah kediaman Ki Buyut sekaligus tempatnya untyuk memimpin masyarakat dan mengajarkan agama sehingga di tempat ini didapati juga balai pertemuan dan masjid. Selain mengunjungi tempat ini untuk berziarah yang berpuncak pada saat perayaan Maulud Nabi, masyarakat luas membangun afiliasi dengan Kramat ini secara khas yakni dengan memperbarui secara berkala atap pada bangunan-bangunan di kompleks ini. Lebih dari 20 bangunan dengan berbagai ukuran diperbarui secara berkala. Penggantian tersebut dilakukan dalam upacara besar yang melibatkan puluhan ribu orang yang bekerja dan berkontribusi sukarela. Penduduk setempat yakin bahwa tradisi ini sudah dijalani sejak pembangunan Kramat ini hingga sekarang. 23 Figur 1.4. Pemasangan atap alang-alang di Trusmi Di Kramat Trusmi bangunan memiliki dua jenis bahan penutup atap. Sebagian menggunakan penutup atap sirap kayu jati (Tectona grandis), sebagian yang lain menggunakan penutup atap rumput alang-alang (Imperata cylindrica). Bangunan beratap alang-alang diganti penutup atapnya setiap 2 tahun sekali, yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun. Bangunan beratap sirap diganti setiap 8 tahun sekali dengan pelaksanaan bertahap setiap empat tahun sekali. Dalam kajiannya tentang prinsip pelestarian cagar budaya Kramat Buyut Trusmi, Kwanda (2012: 153-158) menyimpulkan bahwa berbeda dengan metoda pelestarian konvensional yang menekankan pada keaslian bendawi (tangible authenticity), pelestarian dengan pembaruan meterial seperti di Trusmi menekankan pada keaslian tak bendawi (intangible authenticity) yang ada di benak masyarakat dan dijaga oleh para pemuka dan pengelola Kramat. Hal ini dilakukan dengan motivasi: melestarikan nilai spiritual Kramat, menjaga ketokohan Ki Buyut Trusmi dan melestarikan nilai-nilai sosial dalam bergotong royong. 24 Dengan demikian, praktik berarsitektur yang berupa pembangunan berulang secara berkala di Kramat Buyut Trusmi ini menyandang: a) nilai teknikal untuk menangani material khusus tersebut, b) nilai spiritual dan simbolis dalam kaitannya dengan peran Kramat sebagai tempat peziarahan dan situs cikal bakal, dan c) nilai sosial dalam kaitannya dengan gotong-royong secara rutin dalam skala besar. Praktik yang berlangsung secara meluas dan nilai yang serba cakup (komprehensif) ini menjadikan entitas fisik arsitektur Kramat Buyut Trusmi dan praktik yang inheren di dalamnya relevan untuk dikaji dalam upaya mengembangkan teori arsitektur agar menjadi lebih inklusif. Kramat Buyut Trusmi jelas bukan bangunan yang lazim dibangun dan dijumpai sehari-hari di lingkungan Desa Trusmi atau di wilayah Cirebon. Kompleks ini dan beberapa bangunan lain yang menyertainya penting untuk dikaji sebagai bangunan asal muasal atau cikal bakal. Pemahaman dan spekulasi tentang bangunan asal muasal menduduki peran yang penting dalam pengembangan teori arsitektur (Rykwert, 1981 dan Forty, 2006). Dalam kajian arsitektur terdapat paradoks antara cara pandang yang bersifat evolusionis yang memandang bahwa arsitektur yang paling mutakhir adalah yang paling baik dan cara pandang yang menekankan pada bangunan asal muasal sebagai yang paling otentik dan hakiki sehingga menjadi rujukan yang paling penting untuk perkembangan arsitektur. Le Corbusier (1925) misalnya mendudukkan teknologi sebagai hal yang terpenting yang mengarahkan kemajuan arsitektur tapi sambil mengajukan bahwa pada bangunan asal muasal yang bersahaja di Perancis kita dapat menemukan prinsip-prinsip yang hakiki dalam berarsitektur. Dalam bukunya tentang pentingnya model asali, Rykwert (1981: 2) mengkaji secara luas arti penting bangunan asal muasal yang menginspirasi perkembangan arsitektur karena diyakini memiliki prinsip-prinsip yang hakiki. Forty (2006: 3-14) meninjau ulang kajian tentang arsitektur primitif yang menjadi rujukan tersebut dan menegaskan bahwa 25 gagasan tentang bangunan primitif tetaplah membayangi dan menantang untuk ditafsirkan hingga saat ini. Dalam kajian budaya Nusantara, Rassers (1982: 217-250) mengajukan rumusan tentang rumah asali di Jawa yang mengungkapkan prinsipprisnip budaya dan pengorganisasian sosial dalam masyarakat Jawa. Bangunan primitif dispekulasikan, ditelaah dan dijadikan bagian penting dari argumen tentang prinsip-prinsip arsitektur dengan banyak cara. Vitruvius di abad pertama mengkajinya sebagai figur ideal yang asali yang dirumuskan secara spekulatif verbal seperti yang dilakukan. Laugier di abad ke-18 mengkajinya secara spekulatif dengan gambaran visual. Sementara, Semper di abad ke-19 mengkaji bangunan secara nyata seperti yang dilakukan terhadap gubug dari Karibia meskipun hanya dijumpai dalam pameran. Kramat Buyut Trusmi yang dibangun beratus tahun silam dan dilestarikan dengan cara yang khas memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengkajinya sebagai bangunan asal muasal; bukan hanya sebagai sosok fisik yang dibangun di masa silam yang jauh tapi juga sebagai praktik membangun yang tetap hidup hingga sekarang. Arsitektur sebagai benda serta arsitektur sebagai proses dapat dikaji secara saling melengkapi di Trusmi untuk mengembangkan teori arsitektur secara lebih komprehensif. 1.4. Sifat Tak-Panggah dalam Arsitektur: Beberapa Definisi Operasional Dalam kajian ini, untuk menyebutkan sifat permanen yang sekaligus berarti tak dapat dipindah dan tak bertahan lama dipergunakan istilah “panggah” yang berasal dari Bahasa Jawa. Dalam Bahasa Jawa, “panggah” bermakna: 1. kukuh sêntosa; 2. ora owah gingsir (Poerwadarminto, 1939). Lebih lanjut, Robson dan Wibisono (2002) dalam Javanese-English Dictionary mengartikan “panggah” sebagai: 1. to stand firm; 2. remaining as before, enduring, still going strong. Sebagai konsekuensinya, untuk lawan kata “panggah” yang bermakna tidak tetap (impermanent), dapat dipindahkan (portable), dapat disesuaikan (adaptable) dan ephemeral (sementara) dipergunakan istilah “tak-panggah”. Sifat ini diungkapkan 26 sebagai kata benda abstrak dengan istilah “kepanggahan” dan “ketidakpanggahan” sebagai lawannya. 1.5. Teori Arsitektur di Antara Kepanggahan dan Ketidak-panggahan Kepanggahan dan ketidak-panggahan adalah dua sisi arsitektur yang senantiasa ada. Dalam khasanah Teori Arsitektur, kepanggahan mendapatkan posisi yang dominan sebagai bagian esensial dari arsitektur. Sementara, ketidak-panggahan dipandang sebagai hal yang marjinal atau primitif yang akan dikembangkan lebih lanjut secara evolutif sehingga menjadi kepanggahan. Untuk itu diperlukan kajian teoretik yang bersifat serba cakup tentang kepanggahan agar dapat mengajukan kajian kritis dengan mengangkat posisi ketidak-panggahan. 1.5.1. Kepanggahan: Tempat dan Tapak Salah satu dari jabaran tentang kepanggahan adalah menetap berada di suatu tempat (place). Tempat menjadi pangkal tolak kemapanan yang memungkinkan suatu obyek dalam hal ini arsitektur berkedudukan di dunia nyata dalam jangka waktu yang lama. Tempat adalah pernyataan lokasi yang berkelindan dengan ruang (space). Ahli geografi, Tuan (1977: 5), menegaskan karakteristik tempat yang berbeda dengan ruang meskipun keduanya berlandaskan pada pengalaman (experience). Perbedaan mendasar antara keduanya adalah ruang bersifat lebih abstrak sehingga dipahami sebagai relasi sedangkan tempat bersifat lebih nyata sehingga dipahami sebagai benda. Meskipun menekankan pada perbedaan antara keduanya, dia menyatakan bahwa tempat dan ruang saling menggantungkan keberadaannya yang menjadikan keduanya selalu ada berdampingan. Secara antropomorfis, Tuan (1977: 6) membedakan ruang dan tempat dengan menyatakan bahwa ruang menekankan pada pergerakan (movement) sedangkan tempat tempat menekankan pada perhentian (pause). Pada perhentian itulah ruang ditransformasikan menjadi tempat. Cresswell (2008) memahami saat memiliki dimensi perhentian dan memiliki karakteristik sebagai tempat, suatu lokasi dapat dimuati dengan makna. Salah satu ciri pemuatan makna adalah kita dapat 27 menamainya, “naming is one of the ways space can be given meaning and become place” (h. 9). Norberg-Schulz (1980, 1985) mengembangkan pendekatan fenomenologis untuk memahami lebih jauh hakekat berhenti untuk menyatakan suatu tempat dan berikutnya membentuk kediaman (dwelling) secara bermakna. Norberg-Schulz (1991) menyatakan bahwa dia bertumpu pada Edmund Husserl yang memahami perwujudan bendawi (the thing) dalam kaitannya dengan kesadaran manusia dan Martin Heidegger (2001) yang menginvestigasi lebih lanjut perwujudan tersebut sebagai keberadaan di dunia (being in the word). Setelah manusia berhenti pada suatu tempat dan mewujudkan kemapanannya dia perlu untuk menghayati makna tempat tersebut secara mendalam yang menjadi landasan baginya untuk mengembangkan keberadaannya tersebut. Norberg-Schulz (1980) memahami “jiwa” yang membentuk karakter suatu tempat sepanjang masa ini sebagai genius loci. Arsitekur, dalam kaitannya dengan genius loci adalah “architecture means to visualize the genius loci, and the task of the architect is to create meaningful places, whereby he helps man to dwell” (Norberg-Schulz, 1980: 5). Sejalan dengan penyataan tersebut, ahli geografi, Relph (1976: 3) menegaskan bahwa lebih dari sekedar di mana sesuatu berada, suatu tempat adalah lokasi plus segala sesuatu yang ada pada lokasi tersebut yang saling berkait sehingga membentuk suatu fenomena yang bermakna (meaningful phenomenon). Penghayatan oleh manusia (human experience), bagi Relph (1976) adalah syarat asasi dalam pembentukan nilai penting suatu tempat bagi seseorang. Intensitas penghayatan inilah yang menentukan perasaan di dalam (“insideness”) terhadap tempat tersebut. Unwin (1997: 15) menegaskan bahwa, “Place is to architecture, it may be said, as meaning is to language” (penekanan sebagaimana aslinya), karena meyakini bahwa “pengidentifikasikan tempat” (identification of place) adalah tujuan yang paling fundamental dalam penciptaan arsitektur. Meski tanpa mengutip NorbergSchulz, Unwin juga mengajukan gambaran tentang manusia pertama yang berkelana dan berhenti untuk membentuk tempat yang bermakna. Namun demikian dia 28 merelatifkan perhentian tersebut dengan mengatakan bahwa berhenti itu dapat untuk semalam atau selamanya. Tapak (site), sebagai salah satu wujud dari tempat dan ruang, tidak pernah sepenuhnya terisolasi, dapat dipahami secara terpisah dan dikembangkan tanpa memberi pengaruh pada sekitarnya. Burns dan Kahn, (2005: x-xii) dalam mengkaji “bagaimana tapak dilibatkan dan dikonsepkan melalui perancangan” mengidentifikasikan tiga area pengaruh. Pertama adalah area kontrol yang ada di dalam batas-batas legal suatu tapak. Area ini adalah tapak yang biasanya ditangani dalam perancangan. Yang kedua adalah area pengaruh yang secara langsung yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh rancangan. Yang ketiga adalah area efek, yang terdampak secara luas oleh rancangan tersebut. Tapak adalah konstruksi antara yang bersifat sementara yang terbentuk ketika suatu lokasi diinetervensi oleh manusia dan dieksploitasi untuk kepentingannya melalui perancangan. Untuk dapat dirancang dan dibangun, tempat yang bersifat elusif karena menyandang kompleksitas makna dan hubungan harus disederhanakan, disingkirkan beberapa aspeknya sehingga memungkinkan untuk dimuati dengan program baru dan dibangkitkan narasi baru atasnya. Dalam penyederhanaan itulah suatu tempat berubah menjadi tapak. Beaumegard (2005: 55) merumuskan bahwa dalam pembangunan, skenario yang paling mungkin adalah “suatu tempat diubah menjadi tapak untuk kemudian diubah lagi menjadi tempat” ketika pembangunan usai dan tapak kembali menjalin hubungan yang kompleks secara internal maupun eksternal. Arsitek terkemuka, Holl (2000) mendudukkan tapak dalam posisi yang sangat penting dalam perancangan arsitektur melampaui karakteristik fisisnya karena baginya Arsitektur dan tapak haruslah memiliki hubungan yang dapat dihayati, suatu kaitan metafisis, suatu kaitan puitis” “Architecture and site should have an experiential connection, a metaphysical link, a poetic link” (Holl, 2000: 10). Menurutnya, bangunan dan tapak saling bergantung sejak awal mula arsitektur. Berbeda dengan musik, patung atau lukisan, bagi Holl arsitektur adalah seni yang 29 tidak bergerak (non-mobile) sehingga penghayatan terhadap arsitektur bergantung pada penghayatan tempat kedudukannya. Lebih dari sekedar salah satu unsur penciptaan, tapak adalah landasan fisis dan metafisis bagi penciptaan arsitektur. 1.5.2. Kepanggahan dan Perwujudan Bendawi Perwujudan bendawi arsitektur yang terdiri atas susunan komponen bangunan mendapatkan status ontologisnya dalam kajian tentang tektonika. Dalam kajian tektonika, material memiliki landasan keberadaannya secara estetis, fungsional maupun filosofis. Dalam disertasinya tentang teori tektonika, Rizutto (2010: 1) menyajikan pembagian kajian tektonika dalam teori arsitektur Barat ke dalam tiga masa, yakni: 1) Classical Tectonics yang diturunkan dari filsafat klasik, 2) Rational Tectonic yang bertumpu pada filsafat sains, serta 3) Poetic Tectonics yang dikembangkan oleh gerakan Kontra Pencerahan dan Romantik Jerman. Dalam wacana arsitektur di masa tersebut, keyakinan dan nilai-nilai tradisional yang melandasi arsitektur klasik dipertanyakan secara mendasar. Arsitektur tidak semestinya didasarkan pada selera dan kecenderungan pribadi serta polesan beberapa pernak-pernik dari masa silam tapi harus memiliki dasarnya yang pasti dan rasional. Untuk menjawab “upaya pencarian kepastian” ini diperlukan argumen rasional yang dirumuskan secara sederhana dan mengandung keniscayaan tak terbantahkan. Di abad ke-18, Laugier (2004: 333-339) seorang biarawan dari Ordo Benedictine melalui tulisannya “Essai sur l’Architecture” berupaya menjawab hal ini. Dia berargumen bahwa arsitektur, sebagaimana dalam pelbagai cabang seni, semestinya dikembangkan berdasarkan prinsip dasar yang dijumpai di alam yang terbentuk melalui proses yang secara jelas mengindikasikan aturan-aturannya. Dengan kedekatannya kepada alam dengan pemahaman alamiahnya yang tak tercemari oleh hal-hal lain, manusia, dalam pandangan Laugier, membangun pondok asal-muasal (primitive hut) sebagai bentuk arsitektural yang paling alami yang mewujudkan relasi universal antara bentuk dan kebutuhan. Gambaran pondok asal 30 yang bersifat “paradigmatik” yang diajukan Laugier sangat menekankan pada arsitektur yang berdiri kokoh pada tempat kedudukannya, bahkan secara harfiah, lantaran empat pokok pohon tersebut masih bertaut dengan akar yang tetap terhunjam pada tempat tumbuhnya. Sementara Laugier mengajukan gagasan yang bersifat monogenetis yang meyakini bahwa asal muasal arsitektur—dan dengan demikian asal mula peradaban peradaban—adalah tunggal, beberapa teorisi Era Pencerahan yang lain mengajukan gagasan poligenetis atau asal muasal yang jamak. Pertama kali diterbitkan tahun 1797, esai Milizia (2004: 459-466) merumuskan bahwa arsitektur bermula dari tiga karakteristik utama. Karakteristik pertama terwujud dalam arsitektur Mesir yang didominasi oleh tumpukan batu dan memiliki sosok kolosal. Menurutnya karakteristik ini berasal dari rongga bawah tanah dan gua yang merupakan hunian pertama manusia. Karakteristik kedua berkembang dalam arsitektur Jepang dan Cina yang menggunakan material yang ringan dengan wujud arsitektur tenda. Milizia meyakini bahwa arsitektur ini berasal dari masa manusia hidup sebagai penggembala pengembara yang membangun dan memindahkan hunian mereka dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Kota Cina dengan atap genting yang melengkung di matanya lebih mirip kubu perkemahan sementara ketimbang kota yang mapan. Sementara, karakteristik yang ketiga berupa bangunan kayu yang menurutnya adalah model universal bagi arsitektur di dunia kecuali di Mesir, Cina dan Jepang. Bangunan kayu terbukti dapat dikembangkan lebih lanjut dengan baik sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yunani yang menerjemahkan pondok kayu menjadi arsitektur batu yang diunggulkan. Dengan membandingkan ketiganya, secara tegas dia katakan bahwa pondok kayu adalah yang paling utama lantaran memiliki kesatuan dan keragaman “Of these three models presented by nature to art, without doubt the finest is that of the hut, where art finds unity and variety” (2004). Poetic Tectonic berkembang di Jerman sebagai reaksi terhadap para teorisi Era Pencerahan, di antaranya oleh Gottfried Semper (1803-79). Para ahli yang mengembangkan teori bangunan asal muasal—baik yang bersifat monogenetis 31 maupun poligenetis—sebagai rujukan rasional bagi penciptaan arsitektur mengajukan spekulasi tentang bangunan pertama tersebut dan memerikan karakteristiknya tanpa menampilkan bukti fisis yang nyata. Berbeda dengan para teorisi tersebut, Semper tidak mengajukan model bangunan sebagai rujukan namun berupa komponenkomponen asasi bangunan yang dibentuk dengan teknik-teknik tertentu yang dikembangkan berdasarkan upaya manusia untuk mewujudkan tempat kediamannya yang terdiri atas: perapian yang dibentuk melalui pencetakan, lantai yang dibentuk melalui penumpukan, dinding dan selubung melalui anyaman serta atap melalui perangkaian rangka. Gagasan tentang komponen ini dirumuskannya melalui kajian terhadap bangunan nyata yang berupa gubug Karibia yang dianggapnya sebagai salah satu dari kemungkinan asal muasal yang beragam. Frampton (2002) menegaskan arti penting teori yang diajukan Semper tentang mencetak, menumpuk, merangkai dan menganyam, sebagai teori arsitektur yang bersifat aktif lantaran berbasis tindakan sebagai dasar pembentukan bangunan dan komponen-komponennya. Dia bahkan mengajukan teori ini sebagai pengganti triad Vitruvius yang berfokus pada kualitas arsitektur sebagai obyek purna. 1.5.3. Kepanggahan dan Rasionalitas Bentuk Lantaran arsitektur memiliki berbagai bentuk dengan ragam yang nyaris tak berbatas, penciptaan bentuk arsitektural memerlukan suatu pedoman yang memungkinkan arsitek mendapatkan arahan di tengah ketidakpastian. Pedoman ini diperlukan agar arsitek terhindar dari alternatif-alternatif bentuk yang tak memiliki dasar pemikiran yang sahih dan hanya berdasar selera pribadi semata. Bentuk rujukan ini bersifat esensial, rasional dan abadi. Madrazo (1995) mengkaji berbagai teori tentang bentuk arsitektural yang menjadi pedoman rasional dan bersifat paradigmatik ini. Dalam teori-teori tersebut bentuk yang asasi ini disebut sebagai idea, tipe dan struktur. Idea berkembang hingga masa Renaissans, tipe banyak dirujuk pada Era Pencerahan, sedangkan struktur menjadi terminologi penting sejak Era Modern di abad ke-20. 32 Idea bentuk berkembang dari masa Yunani Kuna hingga Renaisans dengan berbagai pendekatan. Plato meyakini bahwa segala hal ihwal yang dapat kita lihat dan kita rasakan berpangkal pada bentuk asali yang ada di dunia ideal yang menyandang nilai metafisis, estetis, logis dan etis. Semua bentuk yang lain hanyalah bayangan tak sempurna dari bentuk asali yang ada di dunia ideal. Aristoteles, di sisi lain, meyakini bahwa idea tersebut inheren ada di dunia benda yang harus digali oleh para pencipta. Bentuk dasar dikonstruksikan berbasis generalisasi dari hasil observasi terhadap realitas bendawi. Bagi para teorisi Renaisans, idea tidak berada di “dunia lain” tetapi melekat dalam akal budi para seniman pencipta. Konsekuensi dari hal tersebut adalah prinsip bentuk sebagai kesatuan antara aspek struktural atau fungsional, aspek sculptural atau ornamental serta aspek geometris atau perseptual yang semula terintegrasi pada masa Yunani kehilangan keseimbangannya pada masa Renaisans (Madrazo, 1995: 374). Wacana bentuk pada Masa Pencerahan didominasi oleh Laugier dan Quatremere-de-Quincy. Bagi Laugier (2004), bentuk paradigmatik tidaklah bersifat statis dan tak bisa berubah seperti yang dipahami ara teorisi Klasik dan Renaisans. Baginya, bentuk berasal dari prinsip kerja alam dan arsitek semestinya mengimitasi prinsip kerja tersebut guna mendapatkan arsitektur yang baik. Bentuk gubug asal yang dia ajukan sebagai model esensial memiliki nilai penting bukan pada perwujudan bentuk fisis itu sendiri namun pada kemampuan bentuk tersebut dalam memanfaatkan dan menanggapi alam. Cabane atau gubug yang digambarkan Laugier sebagai hasil karya naluriah manusia dalam menanggapi alam memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, bahwa bentuk fisis dapat mewujud sebagai yang konseptual. Kedua, bangunan yang paling bersahaja adalah yang paling mendekati yang ideal. Ketiga, proses kreatif dilakukan melalui imitasi prinsip kerja ketimbang imitasi bentuk. Quatremère-de-Quincy (1998) yang menulis di akhir abad ke-18 adalah teorisi yang pertama kali mengajukan tipe atau type sebagai hal yang utama dalam wacana tentang bentuk. Quatremère memandang penting gubug Laugier sebagai hasil 33 karya akal budi manusia yang berupa bentuk abstrak yang diturunkan dari bentuk sensibel atau dapat dicerap secara inderawi. Tipe berkembang secara evolutif dari gua yang menginspirasi arsitektur Mesir, tenda yang menjadi rujukan arsitektur Cina, dan gubug yang menjadi model arsietktur Yunani. Bias Eropa sangat kentara ketika dia mengajukan arsitektur Yunani sebagai yang paling unggul lantaran gubug yang menjadi rujukannya bersifat panggah dan dapat diimitasi dengan berbagai cara. Berbeda dengan Laugier yang menganggap gubug asal yang dirujuknya bersifat primitif sehingga mencerminkan naluri asali manusia, Quatremère mengajukan gubugnya sebagai ungkapan kecanggihan pada tataran tertentu. 1.5.4. Ketidak-panggahan: Filosofi Dalam kaitannya dengan tempat, Relasi dinamis antara kepanggahan dan ketidak-panggahan dalam tataran filosofis digagaskan oleh Gilles Deleuze (dan Felix Guattari dalam beberapa tulisan) dalam konsep “flow” (aliran) dan “territory” (wilayah) dalam pola pemikiran yang merimpang (rhizomatic) sebagaimana diulas oleh West-Pavlov (2009) dan Ballantyne (2007). Berbeda dari kebanyakan pemikiran yang mengasumsikan ketertataan sebagai basis keberadaan, Deleuze meyakini bahwa semesta yang senantiasa berubah, tersusun dan kemudian terurai secara terus menerus adalah flow yang merupakan kondisi asali pada semua hal ihwal. Dalam suatu keadaan dan kebutuhan tertentu, flow tersebut diarahkan dan ditata sehingga menuju suatu kemapanan dalam suatu proses pewilayahan (territorialization) yang kadang membentuk suatu wilayah atau territory. Untuk menegaskan sifat dinamis dan kesementaraan tatanan Deleuze cenderung menggunakan istilah “territorialization” ketimbang “territory”. Deleuze mengaitkan pemahaman bahwa territory dan tatanan adalah suatu keadaan sementara dalam flow yang terus menerus terjadi dengan keberadaan manusia sebagai pengelana (nomadic state). Hal ini juga sangat relevan dengan cara pandang manusia maritim sebagaimana di Nusantara yang memandang kehidupan di 34 samudera yang senantiasa bergerak adalah yang asali sedangkan pelabuhan yang mapan adalah persinggahan sementara. Dalam ranah geografi, cara pandang dunia yang dinamis ini berkembang di Asia Tenggara yang didominasi oleh kepulauan Nusantara namun sudah sangat terkikis oleh Indianisasi yang mengusung kosmologi berbasis benua dengan gunung yang mapan dan kolonialisasi yang merasionalkan muka bumi sehingga bisa diukur dan dikapitalisasi. Widodo (2009) menegaskan karakter “fluid” dari peradaban berbasis akuatik di Asia Tenggara dan sebelum kedatangan peradaban India dan Islam. Ahli geografi, Savage (2010) menelaah transformasi karena proses Indianisasi yang terjadi di Asia Tenggara ini sebagai suatu perubahan “from aspatial communities to cosmic kingdoms”. Sementara, dengan mengangkat kasus yang terjadi di Thailand, Winichakul (1994) mengamati bahwa kesadaran keruangan dan kewilayahan yang mapan terjadi berbarengan dengan pengaruh ekonomi Barat, penemuan teknik pemetaan dan kolonialisme. 1.5.5. Ketidak-panggahan: Utopia berbasis Teknologi Teknologi memungkinkan manusia untuk membuat perubahan dengan mudah. Percepatan teknolgi di era industri menjadikan manusia memiliki gambaran baru tentang kecepatan perubahan yang dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan utopia yang ingin dicapai. Perang Dunia I adalah peragaan teknologi pertama kali dalam skala besar. Pesawat tempur dan aneka persenjataan bermesin dilibatkan dalam konflik global ini sehingga memicu cara pandang baru dalam berbagai cabang ilmu. Antonio Sant’Elia, seorang arsitek Italia yang aktif sejak sebelum PD I, mengembangkan gagasan tentang arsitektur masa depan yang dipicu oleh teknologi yang memungkinkan perubahan cepat. Dia memamerkan sketsa-sketsa yang dijudulinya sebagai Kota Masa Depan (Citta Nuova). Arsitektur baru yang digambarkannya berupa bangunan-bangunan berbentuk kurva yang lugas tanpa rinci dan ornamen. Kelugasan ini bukan hal baru mengingat beberapa tahun sebelumnya Otto Wagner dan Adol Loos sudah mengajukan ciri ini. 35 Hal terpenting yang diajukan Sant’Elia adalah kecepatan perubahan yang sangat cepat yang dipicu oleh akselerasi teknologi. Pernyataan radikal ini dituangkannya dalam tulisan provokatif yang berjudul The Futurist Manifesto (Sant’Elia, 2007, huruf besar sebagaimana aslinya). Dalam tulisan ini dengan lantang dia mencanangkan bahwa: From an architecture conceived in this way no formal or linear habit can grow, since the fundamental characteristics of Futurist architecture will be its impermanence and transience. THINGS WILL ENDURE LESS THAN US. EVERY GENERATION MUST BUILD ITS OWN CITY. This constant renewal of the architectonic environment will contribute to the victory of Futurism which has already been affirmed by WORDS-IN-FREEDOM, PLASTIC DYNAMISM, MUSIC WITHOUT QUADRATURE, AND THE ART OF NOISES, and for which we fight without respite against traditionalist cowardice. Arsitektur dan bahkan kota haruslah diperbarui terus menerus karena setiap saat dunia berubah. Setiap generasi akan membangun kotanya sendiri yang juga akan diperbarui bagi generasi berikutnya. Di akhir tulisannya dia mempermaklumkan dengan tegas tentang ketidak-panggahan dan kesementaraan, “the fundamental characteristics of Futurist architecture will be its impermanence and transience.” Ketidak-panggahan bukan lagi sifat yang dihidari dengan pemilihan bahan yang seksama dan perwatan bangunan sebaik-baiknya; tapi menjadi hal yang dituju dengan asumsi bahwa perbaikan terus menerus dengan tumpuan teknologi akan memungkinkan hal itu terjadi. Futuris Manifesto mengubah cara pandang bahwa yang dituju bukanlah yang abadi melainkan yang sementara. Meskipun Sant’Elia tidak menghasilkan rancangan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang cara pandangnya yang radikal tersebut, manifesto dan sketsanya tetap menginspirasi para teorisi yang memimpikan masa depan berbasis teknologi tinggi dengan perubahan yang pesat. Ungkapan yang lebih konkret tentang masa depan yang tak-panggah ini berasal dari kalangan Architectural Association di London. Di masa pasca Perang Dunia II sekelompok arsitek menghidupkan kembali gagasan Futurism tersebut 36 meskipun dengan karakteristik yang non-heroik. Kelompok Archigram yang beranggotakan antara lain Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron dan Michael Webb memproduksi rancangan-rancangan eksploratif dan hipotetikal yang mengandalkan pada komponen-komponen ringan, mudah dibongkar pasang, berbasis infrastruktur untuk menghasilkan rancangan moduler yang mudah berubah dan bergerak sehingga memungkinkan adaptasi yang tinggi. Cook (1970) mengeksplorasi potensi bangunan dengan teknologi prefabrikasi yang telah menghasilkan konstruksi dengan bentang sangat lebar di abad ke19 menjadi komponen-komponen bangunan yang terus menerus berubah baik susunan maupun lokasinya. Pameran Archigram bertajuk Living Cities di tahun 1963 memberikan gambaran bagaimana arsitektur yang sering dianggap garda depan ini memahami kota sebagai sistem pengorganisasian ruang dalam skala besar sekaligus mesin penopang kehidupan yang senantiasa berubah (Sadler, 2005). “Plug in City”, Peter Cook 1964 (Sadler, 2005) 37 Di antara karya Archigram yang paling populer di pertengahan tahun 1960an tersebut adalah Plug in City, Walking City dan Instant City. Plug in City berupa struktur rangka yang sangat besar tanpa bangunan hanya tersusun atas sel-sel standar yang ditancapkan pada struktur tersebut. Walking City yang berupa robot raksasa yang berisi ruang hidup di dalam tubuhnya yang dapat berpindah untuk mencari sumber daya baru. Instant City yang berupa tenda yang dipindahkan dengan balon untuk dijatuhkan secara instan di tempat baru. Pendahulu Archigram yang banyak mengembangkan gagasan tentang struktur yang ringan dan adaptif adalah Richard Buckminster Fuller yang mulai berkarya pada tahun 1927. Fuller memiliki perhatian yang mendalam pada isu-isu lingkungan. Dia mengajukan pertanyaan, “Apakah engkau tahu berapa berat rumahmu?” untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menakar sumber daya material yang dipergunakan dalam bangunan. Bagi Fuller, teknologi maju adalah sarana untuk membuat bangunan yang seringan mungkin dan seadaptif mungkin. Perkembangan arsitektur dan teknologi memunculkan pembandingan antara arsitektur modern yang tampak mudah berubah dan arsitektur kuna yang dirancang seolah akan bertahan melintas zaman. Ahli teori arsitektur, Ford (1997) mengajukan pertanyan mendasar, “Apakah arsitektur Modern tak seawet arsitektur tradisional; dan kalau memang benar seperti itu, apakah hal tersebut diakibatkan oleh ideologi, praktik atau keduanya?” Ford menyoroti bahwa setiap komponen Menara Eiffel, sebagai contoh bangunan modern, paling tidak pernah diganti satu kali. Akan tetapi, dia juga mencermati bahwa karya-karya arsitektur masa Renaissans (abad ke-15 dan ke-16 Eropa) sebenarnya mengalami penggantian sebagian besar komponennya pada saat konservasi di abad ke-19. Komponen bangunan memiliki masa pakai yang beragam sehingga baik bangunan kuna maupun bangunan modern sebenarnya mengalami penggantian dan pembaruan yang sama. Namun demikian, dalam kajiannya, Ford berargumen bahwa dalam pandangan dunia Barat, arsitektur identik dengan kepanggahan dan stabilitas, sedangkan kepanggahan diidentikkan dengan massa dan kepejalan. Dengan cara 38 pandang itu maka arsitek dan masyarakat luas tidak dapat menerima kenyataan bahwa bangunan akan usang sebagaimana usangnya mobil dan mesin-mesin lain bikinan manusia. 1.5.6. Ketidak-panggahan: Teknologi dan Sosial Bangkit dari kehancuran setelah Perang Dunia II, Jepang ingin membangun landasan filosofisnya sendiri dalam pengembangan rancangan. Sekelompok arsitek muda pada tahun 1960 mengajukan gagasan yang berjudul Metabolism: The Proposals for New Urbanism yang disajikan pada World Design Conference di Tokyo. Mereka menganggap bahwa kota akan tumbuh dan bertransformasi dalam suatu proses evolutif sebagaimana yang dialami oleh makhluk hidup (Lin, 2010). Didasarkan pada filsafat Zen-Buddhism yang menganggap bahwa segala sesuatu pada hakekatnya berjiwa, para tokoh gerakan Metabolisme menggagaskan bahwa kota sebagai benda terbesar buatan manusia sejatinya adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus. Kemajuan ekonomi dan percepatan teknologi yang dialami oleh Jepang pada saat itu menjadikan gambaran masa depan berbasis teknologi ini menjadi populer. Bangunan tumbuh seperti pohon dengan reranting dan cecabang yang menjangkau langit atau permukaan lautan adalah gambaran populer tentang wujud visual gagasan arsitektural dan urbanisme dari kalangan Metabolisme ini. Krisis kualitas hidup di lingkungan perkotaan pada masa itu memicu gagasan utopian tentang kota yang tumbuh dengan metafora organisme yang memiliki bagian-bagian utama yang relatif tetap dan bagian-bagian yang tumbuh, bertambah dan berubah. 39 Model “City in the Air” yang diajukan Arata Isozaki dalam gerakan Metabolisme pada tahun 1961 (Lin, 2010) Arsitektur yang menekankan pada pertumbuhan adan adaptasi dalam konteks yang lebih realistis dikembangkan oleh John Habraken dan kelompok Open Building. Pertama kali memublikasikan gagasannya pada tahun 1961, Habraken berfokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan massal yang mampu beradaptasi terhadap kebutuhan warga. Dalam pemikiran Habraken, masa depan penuh dengan ketidakpastian sehingga kemampuan perancang untuk dapat memastikan dan memenuhi kebutuhan di masa mendatang sangatlah terbatas. Untuk itu arsitektur dalam arti yang luas—dari kota sampai interior ruangan—perlu untuk dirancang sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi secara berjenjang di masa mendatang. Habraken (1998) memandang perkara ini dari sisi teknologi yang memungkinkan pertumbuhan tersebut dapat dilaksanakan, tapi lebih penting lagi adalah dari sisi sosial. Mengelola pertumbuhan adalah mengelola kewenangan kontrol perubahan pada tiap level, yang terdiri atas struktur yang tetap dan infill yang berubah. Level urban, level kelompok rumah, rumah, interior berturut-turut menunjukkan derajat kewenangan yang makin mendekati ke arah pengguna terakhir (end user). 40 1.6. Permasalahan Dari kajian komparasi teori arsitektur di atas dapat disimpulkan bahwa teori arsitektur didominasi oleh pemahaman tentang arsitektur sebagai produk yang panggah dan paripurna. Seusai dibangun, arsitektur memiliki wujud yang paling sempurna sehingga masa berikutnya adalah upaya untuk memanfaatkan dan mengawetkannya. Seiring dengan percepatan teknologi di era industri modern, berkembang wacana teoretik tentang arsitektur yang beradaptasi secara radikal, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan teknologi. Namun demikian, ketak-panggahan yang didasarkan pada material yang mudah lapuk (perishable materials) pada masyarakat non-industrial belum mendapat perhatian yang memadai. Kramat Buyut Trusmi memiliki komponen-komponen tak-panggah dengan material yang mudah lapuk adalah realita empiri yang sangat berbeda dengan pelbagai idealisasi teoretis tersebut. Kompleks ini melibatkan intervensi terus menerus dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperbaruinya. Lingkungan dengan karaktersitik fisik dan sosial yang khas ini adalah lokus yang relevan untuk didalami sebagai salah satu praktik berarsitektur yang melibatkan aspek ketidakpanggahan secara intensif. 1.6.1. Pemilihan Teori Sifat ketidak-panggahan berkaitan erat dengan aspek material arsitektur, sehingga dalam trilogi Vitruvius sifat ini dapat diasosiasikan dengan kekuatan atau kekokohan yang diistilahkan sebagai Firmitas. Namun demikian, aspek material yang berorientasi praktikal ini hanyalah salah satu sisi dari teori tentang arsitektur sebagai suatu keutuhan dengan sejumlah aspek yang saling berkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen dan keseluruhan ini disebut Vibaek (2014: 14) sebagai “sistem” dalam teori arsitektur (system in architectural theory). Setiap teori arsitektur memiliki bias yang berkaitan dengan konteks budaya, masa dan paradigma yang melandasinya. Dalam lingkup teori arsitektur Barat saja, Vibaek (2014: 16) menjumpai keragaman yang sangat tinggi dalam komponen-komponen sistem ini. 41 Di tengah varian komponen-komponen sistem dalam berbagai teori arsitektur, Kruft (1994: 14) dalam kajiannya tentang sejarah perkembangan teori arsitektur menengarai adanya kecenderungan perumusan teori tentang arsitektur sebagai suatu keseluruhan yang utuh (integrated whole) dengan komponen yang terdiri atas aspek estetis, aspek sosial dan aspek praktikal. Kajian ini berupaya mengembangkan teori arsitektur yang telah ada yang meliputi aspek estetis, sosial dan praktikal dengan melibatkan aspek ketidak-panggahan sehingga menjadi teori yang lebih inklusif. Dari masa teori arsitektur di masa klasik sebagaimana dirumuskan oleh Vitruvius hingga teori arsitektur di masa modern seperti yang daijukan oleh John Ruskin dan Le Corbusier, arsitektur diperlakukan sebagai suatu wujud final dari proses penciptaan. Sebagai suatu karya paripurna, arsitektur diidealisasikan untuk bertahan dalam kondisi sebagaimana saat usai diciptakan, tak ada yang perlu ditambahkan, diubah atau dikurangkan dari mahakarya ini. Dengan cara pandang tersebut, setiap keterlibatan yang berdampak pada perubahan fisik terhadap aristektur dianggap sebagai suatu kekurangan atau kelemahan terhadap produk asal dan upaya mempertahankan wujud asali di masa berikutnya. Sementara, ketidak-panggahan dalam arsitektur khususnya yang melibatkan komponen-komponen dengan bahan tak awet memerlukan keterlibatan terus menerus dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan perbaikan dan penggantian komponen-komponen tersebut. Untuk membangun teori arsitektur yang melibatkan ketidak-panggahan diperlukan landasan teori yang menekankan pada arsitektur sebagai suatu proses yang terjadi secara berkesinambungan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meliputi aspek ketidak-panggahan. Berdasar pertimbangan tersebut di atas dalam kajian ini, seleksi teori arsitektur yang akan dikembangkan melalui kajian tentang Kramat Buyut Trusmi adalah yang memenuhi kriteria: a) Memiliki perhatian mendalam terhadap perwujudan material arsitektur, 42 b) Memiliki komponen teori arsitektur yang berkaitan dengan aspek estetika, sosial dan praktikal, dan c) Menekankan pada proses berkesinambungan ketimbang produk final sehingga adaptif terhadap perubahan setelah penciptaan. Di antara teori arsitektur yang berbasis proses adalah teori “The Process of Architecture” yang dirumuskan oleh Klassen (1990) dan teori “The Presence of Architecture” yang dirumuskan oleh Norberg-Schulz (2000). Kedua kajian ini berlandaskan pada paradigma fenomenologi yang berfokus pada realitas bendawi lingkungan dan diri manusia, to the things themselves, untuk dapat merumuskan kebenaran. Mengingat ketidak-panggahan pada dasarnya pertama-tama melekat pada sifat bendawi arsitektur maka teori-teori ini memiliki dasar yang relevan untuk dikembangkan dalam kajian ini. Teori proses yang diajukan oleh Klassen (1990) mengkritisi dan mengembangkan teori arsitektur yang bertumpu pada penafsiran karya seni. Dia berargumen bahwa pembuatan karya arsitektur tak sepenuhnya aktif dan penikmatan arsitektur tak sepenuhnya pasif. Kedua belah pihak dapat bertukar peran dan membangun arsitektur melalui aktivitas fisik dan mental. Dalam cara pandang prosesual ini, keterlibatan manusia dalam arsitektur sebagai aktivitas mental terjadi secara berkesinambungan. Pembuat juga berperan sebagai pengguna yang sudah mulai menggunakan saat arsitektur masih dalam proses pembuatan, sementara pengguna yang secara mental memiliki juga kapasitas untuk membuat arsitektur juga berperan untuk terlibat dalam proses menggunakan secara mental saat dia mengalami arsitektur. Pertukaran ini memiliki kesejajaran dengan pembaca yang sejatinya juga menulis dalam benaknya sembari dia menikmati bacaan, sebaliknya pengarang membayangkan dirinya sebagai pembaca saat menulis. Masing-masing dari kedua teori tersebut berisfat komprehensif sehingga sebagai suatu sistem arsitektur. Teori Klassen (1990) tentang The Process of Architecture terdiri atas making (membuat), experiencing (mengalami) dan understanding (memahami) arsitektur. Sementara, teori Norberg-Schulz (2000) 43 tentang The Presence of Architecture berunsur use (penggunaan), comprehension (pemahaman) dan implementation (penerapan) arsitektur. Trilogi teori sistem arsitektur Kruft (1994: 14) yang terdiri atas aspek: praktikal, sosial dan estetis dapat dipergunakan sebagai kerangka pembandingan teori Klassen (1990) dan Norberg-Schulz (2000). Aspek praktikal yang berorientasi pada tindakan untuk merealisasikan arsitektur secara nyata dapat disejajarkan dengan aspek “membuat” dari Klassen dan “penerapan” dari Norberg-Schulz. Kedua aspek ini meliputi tindakan untuk mewujudkan suatu gagasan yang abstrak menjadi realitas bendawi yang bermakn. Aspek sosial yang berfokus pada interaksi antara arsitektur dan manusia di sekitarnya berkesesuaian dengan “mengalami” dari Klassen dan “penggunaan” dari Norberg-Schulz. Aspek “estetika” sebagaimana dirumuskan Kruft memiliki dimensi keindahan dan intelektual yang berkaitan dengan “memahami” dari Klassen yang memosisikan keindahan sebagai suatu jenis tindakan memahami yang sublim, dan “pemahaman” dari Norberg-Schulz. Tabel 1.1. Komparasi Komponen- komponen Teori Sistem Arsitektur Kruft (1994) Practical Social Aesthetic Klassen (1990) Making Experiencing Understanding Norberg-Schulz (2000) Implementation Use Comprehension 1.6.2. Rumusan Masalah Bagaimana memahami peran ketidak-panggahan dalam arsitektur dalam lingkungan binaaan dan praktik berarsitektur di Kramat Buyut Trusmi, Cirebon untuk mengembangkan pemahaman teoretik tentang totalitas arsitektur melalui peluasan Teori The Process of Architecture (Klassen, 1992) dan Teori The Presence of Architecture (Norberg-Schulz, 2000). Pertanyaan tersebut dapat dijabarkan ke dalam: 44 a) Peran ketidak-panggahan dalam aspek praktikal arsitektur (membuat atau penerapan arsitektur). b) Peran ketidak-panggahan dalam aspek sosial arsitektur (mengalami atau penggunaan arsitektur). c) Peran ketidak-panggahan dalam aspek estetika (memahami atau pemahaman arsitektur). Gambar 1.9. Atap Masjid Kramat Buyut Trusmi seusai Buka Sirap dengan sirap baru di sisi selatan dan sirap lama di sisi barat. 1.7. Tujuan dan Manfaat 1.7.1. Tujuan: Hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun pemahaman tentang arsitektur dan praktik berarsitektur di Kramat Buyut Trusmi secara komprehensif dengan menekankan pada aspek ketak-panggahan sebagai masukan bagi pengembangan teori arsitektur. 1.7.2. Manfaat: a) Manfaat yang bersifat teoretik yang didapatkan dari kajian ini adalah: 45 − Mengembangkan Teori Sistem Arsitektur yang lebih komprehensif dengan melibatkan aspek ketak-panggahan, dan − Mengembangkan kerangka teoretik yang lebih komprehensif dan relevan untuk mengkaji praktik berarsitektur di Nusantara. b) Manfaat yang bersifat praktikal yang didapatkan dari kajian ini adalah: − Mengembangkan kajian pemanfatan material tak-panggah, − Mengembangkan kajian pembangunan dengan basis komunal, dan − Mengembangkan kajian tentang daur ulang komponen bangunan 46 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA Disertasi ini disusun sebagai upaya pengembangan teori arsitektur dengan menggali dan menafsirkan praktik berarsitektur di salah satu wilayah Nusantara untuk dapat mengajukan kritik dan pengembangan terhadap teori-teori arsitektur mainstream khususnya yang berkembang di Eropa. Untuk itu, Bab Kajian Pustaka ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi telaah tentang teori-teori arsitektur khususnya yang berkembang di Eropa. Fokus kajian teori arsitektur ini adalah pemahaman tentang kepanggahan dan implikasinya pada ketidak-panggahan di dalam teori tentang totalitas arsitektur. Bagian kedua berisi tentang kajian arsitektur Nusantara khususnya yang melibatkan aspek ketidak-panggahan. 2.1 Teori tentang Sistem Arsitektur dan Aspek Ke[tidak]Panggahan Dalam ilmu arsitektur, kepanggahan memiliki dimensi yang luas dan beragam. Terminologi ini dipergunakan untuk merujuk pada berbagai hal, antara lain: a) Kepanggahan yang bersifat ideal yang berupa gagasan abstrak yang bersifat asali dan tak berubah. Berada di ranah akal budi, kepanggahan ideal ini terungkap bukan dalam bentuk wujud bendawi tapi berupa paparan verbal dan kadang visual. Rumusan yang paling menonjol dari kepanggahan ideal ini adalah yang diajukan Plato sebagai bentukbentuk geometri primer yang menjadi rujukan sempurna bagi semua ciptaan manusia yang tak sempurna. b) Kepanggahan yang bersifat sosial yang berupa keyakinan bersama sekelompok masyarakat tentang keberadaan suatu obyek serta prinsip 47 dan nilai yang dikandungnya sehingga dapat bertahan dan terwariskan melintas generasi. Keyakinan bersama ini terwujud dalam monumen dan bangunan lainnya yang diyakini memiliki kestabilan wujud dan makna sehingga dapat menjadi tonggak bagi perjalanan sejarah manusia yang sarat dengan perubahan. Hal ini menonjol pada teori Rossi (1984) tentang permanence yang didasarkan pada pemahaman bersama dalam pembentukan lingkungan perkotaan. c) Kepanggahan yang bersifat lokasional yang berupa keberadaan suatu bangunan pada tempat tertentu dari awal pembangunannya dan diharapkan menetap secara abadi di tempat tersebut. Kemenetapan ini ini bersifat asasi sehingga menjadi aspek yang esensial untuk memahami keberadaan suatu bangunan sebagaimana secara filosofis dirumuskan oleh Heidegger (Sharr, 2007) dan secara fenomenologis oleh Norberg-Schulz (Shirazi, 2014) d) Kepanggahan yang bersifat bendawi yakni kemampuan suatu obyek fisik ciptaan manusia yang dalam hal ini berupa bangunan untuk bertahan dari perubahan bentuk, kualitas dan keletakan dalam jangka waktu yang lama. Ketahanan fisik yang menjamin keberadaan suatu bangunan ini menjadi dasar bagi pengembangan program dan peran yang diharapkan dari suatu bangunan di dalam masyarakat. Hal ini dirumuskan secara teoretis oleh Ruskin (1849). Kajian ini berfokus pada kepanggahan bendawi sebagaimana disebut di atas. Dalam kepanggahan bendawi ini penting untuk memahami relasi antara suatu obyek bangunan dengan komponen-komponen penyusunnya serta relasi antara suatu bangunan bangunan dan tempat kedudukannya dalam jangka waktu tertentu. Risalah tentang arsitektur seringkali disusun sebagai teori preskriptif yang memberikan panduan untuk memahami dan membuat bangunan berdasarkan paradigma dan nilai-nilai tertentu. Dalam kajiannya tentang 48 sejarah teori arsitektur, Kruft (1994: 12-14) menekankan tentang pentingnya konteks kesejarahan untuk memahami berbagai teori arsitektur sebagai suatu sistem pemikiran tentang arsitektur yang disusun secara tertulis. 2.1.1. Masa Klasik Dan Renaisans a) Vitruvius dan Ragam Kepanggahan Teori Arsitektur diperlukan adalah fenomena yang kompleks melibatkan sangat banyak dimensi kehidupan. Diperlukan penyederhanaan untuk dapat memahami totalitas atau keseluruhan aspek dalam arsitektur. Keinginan untuk dapat menjelaskan arsitektur secara sederhana namun rasional itulah yang menjadikan rumusan ringkas dalam risalah tentang arsitektur yang ditulis Marcus Pollio Vitruvius sekitar dua ribu tahun yang lalu, yang berjudul de Architectura atau sering disebut sebagai Sepuluh Buku (lebih tepatnya gulungan) tentang Arsitektur, memiliki posisi yang sangat penting dalam khasanah dan wacana teori arsitektur. Vitruvius mempersembahkan Risalahnya untuk Kaisar Octavianus Augustus pada suatu masa ketika Kekaisaran Romawi sedang melakukan pembangunan besar-besaran baik di kota Roma maupun di wilayah-wilayah jajahannya. Dalam risalahnya (Buku I, Bagian 3.1) Vitruvius membagi bangunan dalam kategori bangunan privat yang berupa hunian dan bangunan publik yang dimanfaatkan bersama-sama. Bangunan publik dibagi lebih lanjut menjadi bangunan pertahanan (seperti benteng dan kanal), bangunan keagamaan yang berupa kuil–kuil pemujaan, serta bangunan utilitarian yakni tempat perkumpulan, melabuhan, kapal, pemandian, pasar dsb. Pada butir berikutnya (Buku I, Bagian 3.2), Vitruvius menegaskan bahwa semua bangunan tersebut semestinya dibangun dengan merujuk pada kekokohan (firmitas), kegunaan (utilitas) dan keindahan (venustas), “Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ration firmitatis, utilitatis, venustatis.” Vitruvius menjelaskan lebih lanjut tentang kekokohan atau firmitas bahwa perkara tersebut dapat terwujud jika pondasi dibangun di atas tanah yang solid 49 dan bahan bangunan dipilih dengan seksama. Dalam penjabaran ini dia membedakan dua jenis kepanggahan. Yang pertama adalah kepanggahan berupa stabilitas bangunan pada tempat kedudukannya yang dicapai melalui pembuatan pondasi yang baik di atas tanah yang terpilih. Yang kedua adalah kepanggahan berupa keawetan bangunan dan komponen-komponen penyusunnya yang diadapatkan melalui pemilihan bahan bangunan yang tepat. Implikasi dari keduanya adalah bangunan diharapkan akan panggah berada pada suatu tempat tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Vitruvius mengungkapkan kekokohan sebagai suatu kesempurnaan seperti, “dinding yang tanpa cela dibangun untuk bertahan selamanya” atau “kesempurnaan yang dapat bertahan dalam keabadian”. Namun demikian, dia juga menengarai ada kepanggahan yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif berkaitan dengan realitas bendawi komponen bangunan yang memerlukan perawatan dan penggantian. Kepanggahan absolut diungkapkannya dalam paparan tentang benteng yang harus memiliki ketangguhan yang langgeng (lasting endurance), yang bahan bangunannya tak rusak oleh pelapukan, perjalanan waktu dan cuaca. Meskipun terkubur di dalam tanah atau terendam di dalam air, benteng tersebut tetap kuat dan berfungsi selamanya (keeps sound and useful forever) (Buku I, Bagian 5.3). Dengan metoda penyusunan yang tepat, suatu benteng akan cukup kuat untuk bertahan selamanya tanpa kerusakan (strong enough to last forever without a flaw) (Buku I, Bagian 5.8). Selain pada dinding dan pondasi, Vitruvius merumuskan kepanggahan yang bersifat relatif yang dicontohkannya pada genting, rangka atap dan usuk. Namun demikian, perlakuan terhadap komponen-komponen tersebut tidak diulas secara mendalam karena dianggap dapat diganti dengan mudah seberapapun kerusakan yang dialaminya (Buku VI, Bagian 8.8). Trilogi Vitruvius yang paling terkenal dan banyak diulas selama berabadabad tentang rujukan dasar arsitektur yakni kekokohan, kegunaan dan keindahan, 50 tidaklah mendapat kedudukan yang setara dalam risalahnya. Dalam urutan penyebutan, Vitruvius mendudukkan kekokohan dalam posisi pertama sebelum dua aspek lainnya. Dia membahas aspek ini secara mendalam pada Buku II segera setelah pembahasan tentang asas dan prinsip berarsitektur pada Buku I. Bahasan tentang kekokohan ini dianggap berlaku secara universal untuk kesemua tipe fungsi bangunan. Aspek keindahan sangat mencolok dipergunakan sebagai asas untuk pembuatan bangunan keagamaan yang dipaparkan secara rinci pada Buku III dan IV. Sedangkan bahasan tentang bangunan publik yang dikategorikannya sebagai utilitarian didominasi oleh telaah mengenai aspek kegunaan seperti kapasitas bangunan dan kualitas akustik sebagaimana termaktub dalam Buku V. Keseimbangan antara ketiga aspek asasi arsitektur tersebut hanya dijumpai pada Buku VI yang mengulas tentang rumah yang meliputi kenyamanan klimatologis dan berbagai ragam fungsi pada bangunan hunian, keteraturan komposisi hingga pondasi. Dari kerangka risalah Vitruvius tersebut dapat dipahami bahwa aspek kekokohan sangat penting untuk dicermati bagi semua jenis bangunan, sedangkan kedua aspek lainnya hanya dipentingkan pada tipe-tipe bangunan tertentu saja. Risalah Vitruvius yang ditemukan dan diterbitkan kembali di Italia pada abad ke-15 memicu banyak pengkaji dan arsitek untuk mengulas, mengembangkan dan menafsirkan tulisan tersebut, seperti Antonio Filarete, Francesco di Giorgio, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Giacomo Vignola, and Vincenzo Scamozzi. Di antara karya-karya baru tersebut, risalah Leon Battista Alberti adalah yang paling komprehensif (Kruft, 1994: 20). b) Alberti dan Kesempurnaan Ciptaan Masa Renaisans Leon Batista Alberti yang menulis pada tahun 1443-52 mengikuti jejak Vitruvius untuk menstrukturkan risalahnya menjadi sepuluh bagian yang masingmasing bagian dijabarkan lagi ke dalam beberapa bab (Rykwert, 1988 dan 51 Mallgrave, 2006). Dia menyebut aspek tiga-serangkai Vitruvius tersebut sebagai properti atau sifat-sifat dasar suatu obyek dengan urutan yang berbeda sebagai berikut: “be accommodated to their respective Purposes, stout and strong for Duration, and pleasant and delightful to the Sight” (Bagian VI Bab 1). Alberti lebih dikenal sebagai seorang intelektual ketimbang seorang praktisi pembangunan. Dengan demikian, dapatlah dipahami jika dia mendudukkan aspek tujuan atau “purposes” yang bersifat rasional sebagai landasan pertama sebelum menyebut yang berikutnya. Mempersembahkan risalahnya kepada Paus Nicolas V, Alberti menulis dengan tujuan untuk menafsirkan dan menjabarkan gagasan-gagasan Vitruvius secara lebih sistematis dan ilmiah. Tiga-serangkai Alberti bukan hanya menjadi suatu pernyataan tapi juga menjadi kerangka untuk menstrukturkan bagian-bagian bukunya. Pembahasan tentang perkara “stout and strong for Duration” atau “kokoh, kuat dan bertahan lama” menduduki tiga bagian pertama dari risalah Alberti setelah dia membahas tentang dasar-dasar desain. Bagian I berkenaan dengan lokasi dan tempat kedudukan dan bagian-bagian utama fisik bangunan yakni landasan, dinding dan kolom. Bagian II pemilihan bahan–bahan membahas bangunan yang kuat dan awet, sedangkan Bagian III berkenaan dengan teknikteknik pemasangan dan penyambungan material dan komponen bangunan. Dalam penstrukturan ini terlihat paradigma Alberti yang mengaitkan antara kedudukan bangunan pada tapak dan lingkungan fisis di sekitarnya adalah landasan bagi kepanggahan suatu bangunan untk kemudian dikembangkan menjadi susunan material dan komponen yang membentuk bangunan yang bertahan lama. Alberti berpedoman pada ketiga asas Vitruvius dengan prioritasnya sendiri. Dia menegaskan secara eksplisit bahwa asas kenikmatan pandangan adalah yang paling luhur dan yang terpenting (the noblest and most necessary of all) untuk diwujudkan dalam bangunan. Hal ini sesuai dengan judul risalahnya De re Aedificatoria, atau Tentang Seni Bangunan. 52 Secara keseluruhan fokus utama tulisan Alberti adalah kenikmatan pandang yang memiliki dimensi etis, estetis dan moral. Baginya bangunan publik yang nikmat dipandang dan direncanakan dengan baik dapat memberikan kepuasan cita rasa visual, memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat. Bangunan keagamaan bahkan diharapkan dapat mendorong perilaku kesalehan dan menghayati kuasa Tuhan. Bangunan yang nikmat dipandang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keindahan dan ornamen. Di antara keduanya, keindahanlah yang utama. Alberti mendefinisikan beauty atau keindahan “reasoned harmony of all the parts within a body, so that nothing may be added, taken away, or altered, but for the worse”. Definisi ini dengan tegas menyatakan bahwa arsitektur adalah obyek yang sempurna pada saat usai dibangun. Sang arsitek yang memiliki cita rasa yang baik dan kecakapan untuk membangun keselarasan yang rasional akan mampu untuk menciptakan bangunan yang indah dengan pertimbangan yang seksama. Kesempurnaan tersebut bersifat final sehingga tak ada yang bisa ditambahkan atau dikurangkan sesudahnya. Keindahan sempurna ini berimplikasi secara langsung pada idealisasi kepanggahan lantaran suatu bangunan didirikan dengan keyakinan bahwa bangunan tersebut tidak akan berubah selamanya. Setiap bentuk pengubahan baik yang berupa penambahan maupun pengurangan hanya akan menurunkan kualitas bangunan. 2.1.2. Masa pencerahan dan Modern Era Pencerahan menjadikan Eropa di abad ke-17 dan ke-18 semarak dengan upaya para filsuf dan ilmuwan untuk merumuskan prinsip yang mendasar bagi semua hal ihwal. Mengkaji Era Pencerahan sebagai basis intelektual budaya Modern, Dupré (2004) menggambarkan bahwa meskipun secara estetis Era ini tidak banyak menghasilkan karya seni unggulan, namun penuh dengan gagasan dan pemikiran yang gemilang yang menjadi landasan yang kokoh bagi 53 perkembangan Era Modern. Upaya-upaya perumusan dasar pemikiran ini marak setelah René Descartes (1596–1650) menyerukan agar manusia mengerahkan kemampuan nalarnya untuk merumuskan satu hal yang pasti dan tak terbantahkan yang akan menjadi landasan bagi semua penilaian dan tindakan. Immanuel Kant (1724–1804) menegaskan lebih lanjut peran tunggal akal yang mandiri yang merdeka dari kungkungan petunjuk orang lain akan mampu menemukan kebenaran. Dari sisi keilmuan, Isaac Newton (1642–1727) memberikan gambaran ideal bahwa prinsip kebenaran yang mendasar tersebut dapat dirumuskan secara sistematis dan sederhana yang menginspirasi wilayahwilayah keilmuan lain untuk menemukan rumusan yang setara (Grayling, 2008). Newton tidak hanya mengubah gambaran tentang dunia tapi keseluruhan cara pandang terhadap realita (Dupré, 2004: xii). Dalam wacana arsitektur di masa tersebut, keyakinan dan nilai-nilai tradisional yang melandasi Arsitektur Klasik berbasis peradaban Romawi dan Yunani dipertanyakan secara mendasar. Arsitektur tidak semestinya didasarkan pada selera dan kecenderungan pribadi serta polesan berbagai ragam hias dari masa silam tapi harus memiliki dasarnya yang pasti dan rasional. Untuk menjawab “upaya pencarian kepastian” ini diperlukan argumen rasional yang dirumuskan secara sederhana dan mengandung keniscayaan tak terbantahkan. Upaya untuk merumuskan teori yang mampu menjadi landasan obyektif bagi penciptaan arsitektur dan arah bagi perkembangan mendatang makin mengemuka di tengah gencarnya Revolusi Industri pada abad ke-19. Mallgrave (2006) menengarai pada masa tersebut terdapat tiga kecenderungan yakni merumuskan langgam yang tepat untuk zaman yang bergerak cepat, mempertimbangkan peran material dan teknologi baru dalam perkembangan arsitektur, serta memberi peluang bagi munculnya identitas nasional dalam arsitektur. Sebagaimana semua konsepsi mendasar yang diwarisi dari masa silam, konsep tentang arsitektur yang panggah sehingga kokoh dan abadi tidak dapat 54 diterima begitu saja. Konsep ini harus diuji kembali dengan argumentasi rasional yang solid untuk dapat diterima sebagai prinsip pemandu perkembangan arsitektur berikutnya. Para teorisi khususnya di pertengahan abad ke-19 yang berhadapan dengan kecepatan kemajuan teknologi yang tak pernah ada sebelumnya memaknai kembali hakekat membuat bangunan sehingga langgeng, menyusun konstruksi sehingga kokoh dan mengaitkan upaya-upaya tersebut dengan tuntutan kebutuhan esensial manusia. Gagasan-gagasan yang dikembangkan pada masa ini menjadi landasan yang penting bagi pengembangan pemikiran modern dalam arsitektur di abad berikutnya. a) Laugier dan Struktur Pondok Asal di Era Pencerahan Marc-Antoine Laugier (1713-1769) adalah seorang biarawan dari Ordo Benedictine yang melalui tulisannya “Essai sur l’Architecture” (2004) berupaya untuk merumuskan dasar-dasar arsitektur secara rasional. Mengkritisi cara pandang di Eropa yang mengandalkan keterkaitan dengan arsitektur di masa silam sebagai legitimasi bagi penciptaan karya arsitektur, Bapa Laugier berargumen bahwa arsitektur sebagaimana dalam pelbagai cabang seni, semestinya dikembangkan berdasarkan prinsip asasi yang dijumpai di alam. Prinsip ini terbentuk melalui proses yang secara jelas mengindikasikan aturanaturannya. “Simple nature” ini bisa dilacak melalui kajian terhadap kondisi asali manusia saat berada dalam tataran primitif yang hanya mengandalkan naluri alamiahnya semata tanpa bantuan ataupun panduan dari orang lain. Dengan kedekatannya kepada alam dengan pemahaman alamiahnya yang tak tercemari oleh hal-hal lain, manusia, dalam pandangan Laugier membangun pondok asal-muasal (primitive hut) sebagai bentuk arsitektural yang paling alami. Pondok ini mewujudkan relasi universal antara bentuk dan kebutuhan. Laugier menggambarkan pondok ini sebagai empat pokok pohon dengan batang dan akar kokoh yang tertanam dalam konfigurasi segi empat. Bagian atas pohon-pohon tersebut dihubungkan dengan empat batang yang berperan sebagai gelagar. Batang melintang ini menopang cabang dan ranting di atasnya yang tersusun 55 serupa atap pelana. Tiang (post), gelagar (beam) dan segitiga atap (pediment) yang tersusun seperti inilah yang merupakan komponen dan komposisi pokok dan asali suatu arsitektur yang akan menjadi rujukan bagi semua ciptaan berikutnya. Dia menegaskan bahwa dengan mendekatkan model sederhana yang pada dasarnya merupakan model konstruksi ini kesalahan kesalahan mendasar dapat dihindarkan dan kesempurnaan sejati dapat dicapai. Dengan demikian, arsitektur dipandang baik bukan karena menerapkan perhitungan geometri yang diwarisi dari tradisi lama yang menjamin keselarasan namun karena memiliki kejelasan konstruksi dan sistem struktur. Gambaran pondok asal yang bersifat “paradigmatik” yang diajukan Laugier sangat menekankan pada arsitektur yang berdiri kokoh pada tempat kedudukannya. Secara harfiah wujud ini ditampilkan pada ilustrasi halaman pembuka risalahnya lantaran empat pokok pohon tersebut masih bertaut dengan akar yang tetap terhunjam pada tempat tumbuhnya. Pokok pohon dengan bagian bawah yang berupa akar yang telah tumbuh terhunjam secara alami dalam masa yang lama dan bagian atas yang dipangkas sesuai dengan kebutuhan manusia ini adalah titik kritis perjumpaan dan keterpaduan antara “nature” dan “culture”. Bangunan asal ini menjadi ungkapan bahwa “culture” yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi sahih karena langsung terhubung dengan akar-akar prinsip alaminya. Dalam risalahnya, Laugier memosisikan konstruksi bukan sekedar sebagai sarana pragmatis untuk dapat mewujudkan bentuk tertentu dan mengakomodasi kebutuhan tertentu tapi menjadi ungkapan yang paling mendasar dan hakiki yang menjadi landasan untuk penciptaan arsitektur. b) Ruskin dan Landasan Moral bagi Arsitektur yang Abadi Di antara teorisi yang paling menonjol pertengahan abad ke-19 adalah John Ruskin (1819-1900) di Inggris, Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) di Perancis dan Gottfried Semper (1803-1879) di Jerman. Ketiganya memiliki kesamaan dalam menolak Arsitektur Klasik sebagai rujukan tertinggi bagi 56 penciptaan arsitektur. Ketiganya juga meyakini arsitektur haruslah kembali kepada sifat-sifat bendawinya, karena hanya dengan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat tersebut arsitektur yang baik akan dapat ditemukan. John Ruskin berupaya untuk merumuskan teori arsitektur yang sahih tanpa harus menyatakan secara eksplisit tentang penemuan arsitektur baru di zaman yang sedang berubah ini. Dalam buku pertamanya, The Seven Lamps of Architecture (1849), Ruskin menegaskan pentingnya landasan moral bagi penciptaan arsitektur yang ditujukan untuk perbaikan sosial. Dengan sepenuhnya mengabaikan Vitruvius dan para teorisi Renaisans, dia mengundang para patron, arsitek dan pekerja bangunan untuk bersama-sama menciptakan arsitektur unggulan yang dilandasi oleh “kejujuran” yang akan menghasilkan keindahan. Risalahnya disusun dalam format kerangka evaluasi yang dibaginya ke dalam tujuh “lamps” atau “pelita” yang akan mencerahkan arsitektur. Yang pertama adalah “pengorbanan” (sacrifice) yang mengajak semua pihak untuk mengkontribusikan dana yang memadai, kecermatan perancangan, material pilihan dan keterampilan pengerjaan guna mewujudkan suatu karya arsitektur yang terbaik. Kriteria “kebenaran” (truth) berkenaan dengan kejujuran bahan bangunan dan komposisi struktural. Suatu karya arsitektur semestinya menampilkan bahan bangunan apa adanya sehingga tak menyerupai bahan bangunan lain. Begitu pula prinsip dalam komposisi struktural. Suatu bangunan semestinya mengungkapkan bagaimana proses pembentukan dan cara konstruksinya sehingga tak rancu dengan cara konstruksi yang lain. Kriteria “kekuatan” (power) diartikan sebagai kemampuan bangunan untuk tampil secara mengesankan pada pengamatnya. Ruskin membagi kesan tersebut menjadi “agung” yang menunjukkan skala yang besar, ekspresi yang lugas, dan bias cahaya yang dramatik, serta “indah” yang menampilkan keanggunan, kerumitan dan kehalusan. “Keindahan” (beauty) adalah kriteria yang dikaitkan dengan ketepatan penggunaan ornamen agar dapat meningkatkan kualitas penampilan bangunan dan bukan sebaliknya. 57 Adapun kriteria yang kelima adalah “kehidupan” (life) yang dia kaitkan dengan motif, keragaman dan komposisi yang dinamis yang mengesankan kehidupan. “Kenangan” (memory) adalah kriteria keenam yang dikaitkannya dengan nilai puitis dan inspirasional suatu bangunan dari masa silam, baik yang berada di lingkungan perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini mendorong untuk dilakukan pelestarian pada bangunan-bangunan yang menyandang kriteria tersebut. Kriteria yang terakhir adalah “kepatuhan” (obedience) yang menekankan pada evolusi kultural yang menjadi titik tengah antara kebekuan rujukan pada arsitektur masa silam dan kebebasan mengumbar kreativitas bentuk tanpa arah. Dalam kaitannya dengan konsepsi tentang kepanggahan, kriteria pertama Ruskin adalah landasan terpenting. Karena semua pihak telah melakukan “pengorbanan” untuk dapat menghasilkan karya arsitektur terbaik, maka produk dari pengorbanan tersebut adalah sesuatu yang sempurna. Ruskin memandang arsitektur sebagai suatu proses transformatif. Dalam proses ini manusia mencipta dengan mengubah bahan bangunan sehingga terwujud suatu bangunan yang baik dan paripurna. Untuk itu dia mengawali risalahnya dengan Sacrifice atau pengorbanan yang mendorong kita untuk sepenuh hati merelakan material terpilih dan mengkontribusikan upaya terbaik dalam penciptaan arsitektur. Kesungguhan dalam “menginvestasikan” keduanya akan menjadi dasar bagi kualitas arsitektur yang dihasilkan. Berbeda dengan Alberti yang mengangkat figur arsitek sebagai yang memiliki kecerdasan utama sehingga menghasilkan produk rancangan yang paripurna, Ruskin meyakini bahwa kontribusi berbagai pihaklah yang menghasilkan arsitektur yang baik. Kebenaran adalah pelita yang kedua yang akan tercapai jika kita membentuk arsitektur tersebut secara jujur baik dari segi karakteristik materialnya maupun teknik pembuatannya. Batu haruslah tetap tampil sebagai batu, ukiran haruslah dibuat dengan tangan dan bukan dengan mesin yang menghasilkan produk menyerupai kriya tangan manusia. Sekeping terakota yang 58 dibuat dengan kecermatan tangan lebih bernilai dari sebungkah pualam yang dipotong dengan mesin, begitu Ruskin (1849: 57) memberikan contoh tentang keterkaitan antara nilai material dan nilai kekriyaan. Sifat alami bahan dan jejak cara pembuatan semestinya tidaklah lenyap jika arsitektur telah rampung dibentuk. Sekali suatu arsitektur yang baik telah terbentuk maka bangunan tersebut menjadi obyek yang sempurna dan rampung dicipta. Di akhir penciptaan, ketika ketujuh nilai luhur telah terpenuhi, arsitektur menjadi bagian dari keabadian. Bahkan jika pada kenyataannya bangunan dalam jangka waktu yang lama menjadi lapuk dan lekang kita tak boleh memperbaikinya apalagi mengembalikannya kepada kondisi semula. “We have no right whatever to touch them. They are not ours. They belong partly to those who built them, and partly to all the generations of mankind who are to follow us” (Ruskin, 1849: 186). Realitas bangunan yang melapuk tak menyurutkan nilainya sebagai karya arsitektur yang pernah dicipta dengan landasan yang baik. Dengan cara pandang tersebut, Ruskin tidak menafikan realita bahwa seiring dengan perjalanan waktu, suatu bangunan akan mengalami kerusakan alami. Cara terbaik untuk menanggulangi dari kerusakan tersebut bukan dengan melakukan perbaikan pada bangunan tapi mengantisipasinya dengan kembali pada kriteria pertama, bahwa bangunan yang dibuat dengan material, teknik dan kecakapan yang sempurna akan tahan menghadapi kerusakan alami. Kepanggahan menjadi sifat yang niscaya pada bangunan yang diwujudkan dengan pengorbanan dan kejujuran sepenuhnya. c) Viollet-le-Duc dan Kebenaran Metoda Konstruksi Menulis di ambang awal Era Modern di Perancis pada saat yang hampir bersamaan dengan Semper, Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–79) membangun teori yang memberikan dukungan bagi arsitektur untuk dapat menemukan bentuk yang baru seusai dengan perkembangan jaman untuk menandingi kubu Ecolé des Beaux-Arts yang berkutat dengan komposisi bentuk 59 yang didasarkan pada rujukan kesejarahan. Hearn (2003:13) mengajukan ViolletLe-Duc sebagai “bapak sejati arsitektur modern” karena dia adalah teorisi arsitektur yang paling sistematis dan komprehensif setelah Alberti. Sebagaimana Laugier, dia berusaha untuk merumuskan prinsip arsitektur yang abadi dan universal. Prinsip ini haruslah tak terikat pada kecenderungan dan situasi sesaat ataupun pada rujukan kesejarahan yang terikat dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Viollet-le-Duc mengajukan teori bahwa penciptaan arsitektur dipengaruhi oleh dua prinsip, yakni yang bersifat konstan dan yang bersifat variabel. Di antara prinsip yang konstan adalah sifat-sifat alami material, sedangkan di antara prinsip variabel adalah faktor sejarah dan sosial. Dengan penekanan pada yang konstan, dia merumuskan lebih lanjut bahwa membangun, bagi seorang arsitek, adalah menggunakan material sesuai dengan sifat-sifat alaminya yang hakiki guna memenuhi tujuan pembangunan dengan cara yang paling sederhana dan paling kuat. Pada dasarnya, membangun adalah “memberikan kepanggahan pada suatu strukur yang dibangun” (to give the built structure an aspect of permanence) (Viollet-le-Duc, Dictionnaire, dikutip oleh Kruft, 1994: 283). Prinsip-prinsip logis tentang material dan struktur ini diyakini Viollet-leDuc sebagai bersifat abadi, bahkan dapat melampaui realitas fisis empiris obyek yang dibangun. Sebelum banyak menulis tentang arsitektur, dia lebih dikenal sebagai ahli pemugaran bangunan bersejarah. Dengan cara pandang ini, dia mengembangkan pemahaman yang berbeda tentang restorasi bangunan bersejarah. Viollet-le-Duc merumuskan bahwa restorasi pada dasarnya bukanlah mengembalikan suatu bangunan kepada kondisi asli yang pernah ada pada suatu masa tertentu tetapi mengembalikan bangunan kepada prinsip struktural yang paling logis yang diyakininya memiliki kebenaran absolut sehingga bahkan dapat dipergunakan untuk “mengoreksi” bangunan dari masa silam. 60 Dalam risalahnya yang paling komprehensif, Entretiens sur l’architecture yang ditulis menjelang akhir abad ke-19, Viollet-le-Duc (1987) menekankan hal tersebut sebagai “kebenaran” (true) yang harus dicapai dalam arsitektur: In architecture there are two necessary ways of being true. It must be true according to the program and true according to the methods of construction. To be true according to the program is to fulfil exactly and simply the conditions imposed by needs; to be true according to the methods of construction is to employ the materials according to the qualities and properties . . . purely artistic questions of symmetry and apparent form are only secondary conditions in the presence of our dominant principles (Viollet-le-Duc, 1987: 446). Bagi Viollet-le-Duc, prinsip-prinsip tersebut bukan hanya alat bantu untuk mengarahkan rancangan, tapi adalah “kebenaran” yang wajib untuk diungkapkan. Bangunan secara bendawi mungkin akan rusak dan lapuk, tapi “kebenaran” pada bangunan yang dirancang dengan baik akan tetap abadi. Bentuk arsitektur Gothik misalnya yang langsing, menjulang dan terawang, dalam pemahaman Viollet le-Duc tercipta karena pemahaman yang benar terhadap sifat-sifat fisis batu dan prinsip strukturnya yang rasional. Dalam terminologi Vitruvius, Viollet le-Duc hanya berkonsentrasi pada aspek firmitas dan utilitas, sedangkan venustas yang tak terkait dengan kedua prinsip yang pertama hanyalah “secondary condition” yang tak mendapat penekanan yang setara. Dengan cara pandang ini, bangunan yang dirancang dengan struktur yang rasional tidak serta merta menjadi indah. Akan tetapi, tidak ada bangunan yang indah yang tak memiliki struktur yang dirancang secara rasional (Hearn, 2003). Ornamen dan elemen dekoratif lainnya hanya akan mendapat tempat dalam arsitektur sejauh mampu mengungkapkan prinsip-prinsip strukturnya secara estetis. Rumusan tentang kedua “kebenaran” ini memberikan dorongan bagi arsitektur untuk berkembang secara progresif dengan mengambil rujukan yang sesuai dengan jamannya. Kebutuhan manusia sebagai hal yang penting untuk dipenuhi oleh arsitektur secara efisien berkembang secara dinamis. Begitu pula 61 material baru yang dihasilkan oleh industri modern mendapat tempat yang layak dalam arsitektur sejauh kita dapat memahami sifat-sifat fisis asasi material tersebut sehingga dapat menerapkannya ke dalam struktur yang paling logis guna mendapatkan wujud baru arsitektur. Penekanan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia menjadikan Viollet le-Duc lebih mementingkan pada penciptaan ruang melalui perancangan struktur yang rasional dan jujur, ketimbang pada penciptaan bentuk yang estetis. Dia memberikan contoh tentang perancangan auditorium untuk 3.000 orang. Kebutuhan bangunan auditorium itu dipenuhinya dengan merancang bangunan berkubah berangka baja dengan struktur polihedron serupa kubah geodesik yang tampak jelas dari ruang di bawahnya. Bangun polihedron diperhitungkannya sebagai bentuk struktural yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut haruslah tampil secara ekspresif pada ruang dalam. Dengan demikian Viollet-le-Duc menekankan bahwa bangunan yang dapat memenuhi tuntutan fungsi dengan struktur yang rasional dan ekspresif telah memenuhi kedua kebenaran yang mendasar dalam arsitektur. Dengan pemenuhan ini maka keberadaan fisik bangunan layak untuk diabadikan sehingga ketika entitas fisik bangunan tersebut mengalami kerusakan maka dapat dilakukan perbaikan mengingat rujukan logisnya sudah terbentuk sejak bangunan diciptakan. d) Semper dan Kebutuhan Hakiki Berarsitektur Gottfried Semper, sebagaimana Laugier, menyandarkan teori arsitekturnya pada awal mula penciptaan bangunan. Berbeda dengan Laugier yang merumuskan suatu prototipe arsitektur yang dianggap sahih untuk memberikan penjleasan tentang susunan dasar elemen-elemen bangunan, Semper meyakini bahwa asal muasal arsitektur bersifat jamak sehingga dapat memiliki wujud yang beragam. Gagasan Semper tentang kejujuran material yang bersifat rasional juga berkesesuaian dengan gagasan yang berkembang pada pertengahan abad ke-19 yang menjadi landasan bagi rasionalisme struktural arsitektur modern. 62 Hal yang paling asali bagi Semper dalam penciptaan arsitektur bukanlah perumusan prototipe arsitektur yang akan menjadi rujukan melainkan pemahaman terhadap teknik-teknik primordial yang membentuk arsitektur yang didasari oleh kebutuhan asasi manusia. Dengan memosisikan arsitektur sebagai seni terapan yang menggabungkan antara tuntutan pragmatis dan simbolis, Semper (1989) merumuskan teknik-teknik tersebut dalam risalahnya yang tentang elemen-elemen asasi arsitektur. Semper mengajukan empat teknik asali dalam penciptaan arsitektur. Yang pertama dan paling mendasar adalah membentuk tanah liat dengan teknik keramik sehingga menjadi tungku. Dalam pengamatan Semper terhadap sejumlah bangunan awal, tungku perapian adalah landasan fundamental tentang keberadaan manusia yang mapan. Manusia yang berhimpun di seputaran api adalah cikal bakal terbentuknya tatanan sosial. Dalam menjaga keajegan api dalam tungku tersebut manusia membentuk elemen-elemen bangunan lainnya dengan tiga teknik yang paling mendasar. Semper menggambarkan tentang asal muasal bangunan sebagai tindakan komunal: Around the hearth the first groups assembled; around it the first alliances formed; around it the first rude religious concepts were put into the customs of a cult. Throughout all phases of society the hearth formed that sacred focus around which the whole took order and shape. It is the first and most important, the moral element of architecture. Around it were grouped the three other elements; the roof, the enclosure and the mound, the protecting negations or defenders of the hearth’s flame against the three hostile elements of nature (Semper, 1989: 102). Setelah merumuskan teknik membentuk secara plastis untuk membuat tungku, Semper (1989: 102-3)merumuskan lebih lanjut ketiga teknik yang lain. Dengan teknik tumpukan atau pasangan (masonry) manusia menyusun batu sehingga menjadi landasan atau sub-struktur yang akan membentuk pelindungan di bawah. Dengan teknik ketukangan (carpentry) dia mencipta atap yang bersifat tektonis yang melindungi dari atas. Pelindungan dari samping dan pembagian 63 ruang terbentuk melalui teknik menganyam sehingga menghasilkan pelingkup (enclosure). Keempat teknik yang mengasilkan keempat ragam elemen asasi tersebut menjadi pembentuk utama arsitektur. Berpangkal pada upaya bersama untuk membangun perlindungan bagi api agar dapat tetap menyala abadi arsitektur terbentuk melalui teknik-teknik tersebut. Meskipun pembentukan elemen dengan teknik keramik adalah tindakan yang paling asasi dalam arsitektur, yang paling menyita perhatian Semper adalah seni menganyam serupa tekstil sehingga membentuk pelingkup. Semper (2004) menekankan pada pembahasan tentang pembuatan selubung (cladding) dan pelapisan (incrustation) yang seringkali terlewatkan dalam pembahasan arsitektur yang berfokus pada aspek struktural di masa itu. Berawal dari teknikteknik pelapisan rangka yang memberi bentuk dan wujud pada bangunan, Semper menelaah secara mendalam tentang prinsip-prinsip menganyam. Dalam kajian tentang teknik menganyam tersebut, Semper menjumpai bahwa teknik ini mengandung hal yang paling fundamental bagi manusia dalam menciptakan karya-karyanya. Simpul (knot) adalah teknik yang paling asasi yang mengandung “energi” dasar penyatuan unit-unit yang semula terpisah menjadi suatu kesatuan. Bukan hanya secara pragmatis, penyatuan ini juga memiliki muatan kosmis sebagai asal mula tindakan manusia. Ditegaskannya bahwa, “The knot is perhaps the oldest technical symbol and, as I have shown, the expression for the earliest cosmogonic ideas that arose among nations” (Semper, dikutip dalam Hvattum, 2009: 68). Membahas arti penting simpul sebagaimana digagaskan Semper, Hale (2009) mengungkapkan bahwa berbagai mitos penciptaan dan ritual menunjukkan universalitas teknik membuat simpul ini sebagai perwujudan “menjadi” (becoming) yang mengungkapkan tatanan yang muncul dalam ruang dan waktu tertentu. Membuat simpul adalah tindakan fundamental dalam membentuk elemen serupa tekstil yang unik tapi sekaligus berulang-ulang secara 64 bermakna. Simpul adalah upaya manusia untuk menyatukan sehingga menjadi tindakan yang produktif dan bermakna. Dalam memahami arti penting teori Semper tentang pembuatan simpul ini, Hale (2009) mengajukan beberapa hal penting. Perjumpaan antara material dan bentuk dalam proses “menjadi” sebagaimana terwujud dalam pembuatan simpul adalah “tectonic event” yang memberikan gambaran di satu sisi tentang proses penciptaanya, di sisi lain tentang proyeksi ketika bangunan akan berinteraksi dengan penggunanya. Dalam kaitannya dengan kajian tentang kepanggahan ini, Hale (2009) menegaskan tentang pentingnya dimensi temporal dalam proses penciptaan unit-unit dasar yang membentuk arsitektur yang dapat terjadi secara berulang. 2.2 Ketidak-panggahan dalam Kajian Arsitektur Nusantara Minat untuk memahami arsitektur di Nusantara secara lintas wilayah berkembang dengan baik belakangan ini, terutama setelah kajian komprehensif yang dilakukan oleh Waterson tentang “Living House” (1990) yang didasari pada teori Levi-Strauss tentang “masyarakat [berbasis] rumah” atau societe à maison dan kajian Domenig (1980) yang berfokus pada tektonika atap bangunan tradisional Nusantara. Kedua kajian ini memiliki kesamaan dalam upaya mereka untuk merumuskan fitur-fitur arsitektural lintas etnis di Indonesia meskipun yang pertama menggunakan pendekatan antropologis sedangkan yang kedua menggubakan pendekatan tektonis. Dengan mengkomparasikan bangunan-bangunan dengan ujung atap menjorok (protruding gable atau kraggiebel), Domenig (1980) membangun teorinya tentang asal muasal dan evolusi arsitektur di Nusantara. Dia mengajukan hipotesis bahwa arsitektur di wilayah ini pada mulanya adalah gubug yang terbuat dari susunan kayu berbentuk kerucut. Dengan penambahan sepasang tiang, yang kemudian berkembang menjadi empat untuk menandai pusatnya yang sakral serta batang mendatar pada puncak bangunan yang kemudian berkembang 65 menjadi bubungan yang menjorok, sosok dasar cikal bakal arsitektur itu pun berkembang dengan keragaman yang luar biasa banyaknya. Argumen-argumen tektonisnya memberikan pemikiran yang lebih masuk akal ketimbang sekedar berspekulasi bahwa para leluhur membuat atap menjorok dengan merujuk pada bentuk kapal sebagaimana dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Meskipun tak secara langsung merujuk pada kajian Domenig (1980), Prijotomo (2006) dalam karya utamanya (Re)Konstruksi Arsitektur Jawa merumuskan kembali sejumlah hal mendasar dalam arsitektur Jawa yang memiliki keterkaitan dengan teorinya tentang keterkaitan antara komponen bangunan melalui kajian tekstual. Dia menelaah 18 naskah yang kemudian dapat dirunut berasal dari dua korpus saja, yaitu Kawruh Griya dengan 13 resensi serta Kawruh Kalang yang mempunyai 5 resensi. Dia menemukan bahwa beberapa naskah tersebut disebutkan bahwa rumah berbentuk tajug atau beratap serupa piramida adalah asal dari semua bentuk atap lainnya. Dalam telaahnya Prijotomo membangun teori bahwa konstruksi bawah (tiang dan balok) dan konstruksi atas (atap) pada dasarnya berkembang secara terpisah. Bidang yang terbentuk atas susunan gelagar (blandar dan pengeret) dibentuk sebagai pertemuan antara keduanya. Dalam pertemuan inilah bentuk bangunan (dhapur griya) dikembangkan menjadi berbagai ragam dengan penciri utamanya pada bentuk atap sedangkan keempat saka guru atau tiang utama berkembang membentuk ruang-ruang di bawah atap. Kajian lintas wilayah yang tampil berikutnya adalah yang disusun oleh Schefold, Nas, Domenig, Wessing (2008; 2 vol.) Kajian tentang hubungan antara kontinuitas dan perubahan diakronis dalam berbagai arsitektur di Nusantara (khsusunya di Indonesia Barat) dengan mengasumikan Indonesia sebagai “field of anthopologigal studies”. Jarzombek (2013) menyusun kajian tentang First Societies di berbagai penjuru dunia. Kajian tentang arsitektur masyarakat agraris pra-modern di antaranya yang terdapat di Indonesia dengan penekanan pada 66 aspek “global” dengan kerangka lintas sejarah dan satuan keruangan. Dia mengelompokkan kepulauan Nusantara berdasar sebaran hortikultura di kepulauan Asia-Pasifik. Dalam kaitannya dengan kajian tentang ketidak-panggahan ini yang paling relevan adalah buku Domenig (2014). Setelah penerbitan tulisan utamanya lebih dari 30 tahun berselang (Domenig, 1980) tentang “arsitektur atap”, Domenig (2014) memublikasikan Religion and Architecture in Pre-Modern Indonesia yang banyak terkait dengan anasir yang tak panggah dan praktik yang terkait dengan anasir tersebut. Sebagaimana judulnya, Domenig (2014) meyakini bahwa sebagian besar penduduk di kepulauan Nusantara semula memiliki keyakinan dan praktik-praktik terkait keyakinan tersebut banyak memengaruhi cara mereka berarsitektur dan membentuk ruang. Meskipun sebagian besar praktik tersebut telah terhapus dengan datangnya agama-agama universal baru khususnya agama monoteistis seperti Kristen dan Islam serta maraknya modernisme, jejak cara lama berarsitektur tersebut masih dapat dilacak melalui kajian terhadap catatan etnografis, artefak dan sisa-sisa praktik yang masih terlestarikan. Domenig (2014) menggarisbawahi sejumlah hal penting yang terkait dengan ketidak-panggahan yang dipahaminya berkaitan dengan upaya manusia membangun pertalian dengan leluhur secara intensif dalam ruang hidup mereka. Dalam kepercayaan awal ini, pemujaan leluhur pada dasarnya dilakukan dengan menghadirkan arwah mereka yang tinggal di langit di kediaman para pemujanya di muka bumi. Fitur fisis yang pertama dibahasnya dalam kaitannya dengan penghadiran leluhur itu adalah altar pemujaan di ruang terbuka yang berhias dedaunan dan elemen vegetal lainnya. Bersama dengan sesaji yang diletakkan di atas altar, keindahan hiasan dari tumbuhan segar tersebut dipercaya untuk memikat leluhur agar turun ke bumi. Tajuk tetumbuhan segar yang menghiasi altar tersebut dikaitkan Domenig (2014) lebih lanjut dengan pembentukan atap bangunan-bangunan pemujaan yang secara simbolis merupakan penerjemahan dari altar di ruang terbuka tersebut. Pada altar yang terletak di platform tinggi 67 dibuatlah “tangga arwah” (spirit ladder) agar leluhur yang mengunjungi altar turun menjejak bumi kediaman mereka. Sesudah menapak bumi, para leluhur diantarkan melalui “jalur arwah” (spirit pathway) yang dibentuk dengan penanda yang panggah dan tak panggah. Rumah yang dibentuk sebagai transformasi dari altar pengundang arwah yang terbuka berhias dedaunan dibuat dengan ujung-ujung atap yang menonjol serta penutup bidang segitiga atap yang memiliki bentuk ragam hias serupa tumbuhan. Ritus-ritus terkait pemasangan elemen-elemen tersebut memperkuat pemahaman tentang fungsi keagamaan bagian ornamental ini. Lebih lanjut, Domenig (2014) menengarai tentang atap rumah-rumah di Nusantara yang menjulang tinggi atau menjorok jauh sebagai bagian bangunan yang relatif tak stabil. Dia mengajukan argumen bahwa usuk yang berjajar diagonal membentuk atap yang menjulang dan bubungan yang membentuk atap menjorok itu adalah jalur perlintasan arwah leluhur. Gambar 2.1. Rumah Batak Toba dengan elemen tangga dan vegetasi yang kuat (Domenig, 1980: 146) 68 Kajian Domenig (2014) membahas rumah dari berbagai suku di Nusantara tapi sangat sedikit membicarakan Jawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di kepulauan ini. Sementara, kajian Rassers (1982) tentang budaya Jawa yang dipublikasikan pada awal abad keduapuluh menunjukkan fenomena yang serupa. Dengan memelopori paradigme strukturalis yang memosisikan elemen-elemen budaya secara diametral, Rassers (1982) menekankan tentang peran kobongan atau krobongan sebagai elemen esensial dalam rumah Jawa yang dipahaminya terdiri atas dua bagian utama dengan sifat-sifat yang saling bertentangan yakni pendopo dan omah mburi. Krobongan yang ada di dalam jantung omah mburi pada dasarnya adalah “kuil kesukuan” (tribal temple) yang diwujudkan untuk menyambut kehadiran Sri, dewi kesuburan dan leluhur orang Jawa. Secara simbolis, krobongan merupakan manifestasi dari kayon atau pohon hayat. Saat upacara pernikahan ketika krobongan menjadi fokus ritual sebagai pelaminan, tempat ini dihiasi dengan kembar mayang yang dibuat dari dedaunan segar (h. 246). Omah mburi adalah wilayah perempuan sehingga upacara pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak mempelai perempuan difokuskan pada krobongan. Berbeda dengan pernikahan, khitanan yang merupakan upacara yang diperuntukkan, dilaksanakan dan dihadiri oleh laki-laki harus menggunakan tempat selain krobongan yang ada di ranah perempuan. Untuk itu dibuatlah bangunan di luar yang juga disebut krobongan yang biasanya didirikan di dekat pendopo. Kadang bangunan luar ini disebut tratag (bangunan temporer), tarub (bangunan dihias rumbai daun kelapa) atau kebon alas (kebun hutan). Rassers berargumen bahwa bangunan tak-panggah yang dihias dengan dedaunan ini merupakan perwujudan dari rumah leluhur laki-laki orang Jawa sebagai pasangan dari krobongan di omah mburi. Kajian Rassers (1982) tentang arsitektur Jawa dan Domenig (2014) tentang arsitektur berbagai suku di luar Jawa saling menguatkan pemahaman tentang 69 relasi antara ritus penghadiran leluhur, bangunan temporer berhias dedaunan dan rumah kediaman yang melandasi pembentukan lingkungan binaan di Nusantara. 2.3 Landasan Teori: Klassen dan Norberg-Schulz 2.3.1. Landasan Teori: Teori Klassen tentang The Process of Architecture Winand Klassen adalah seorang agamawan dan ilmuwan arsitektur dari Jerman yang mengajar di University of the Phillippines dalam waktu yang lama. Hal ini memengaruhi cara pandangnya terhadap arsitektur yang dipahami sebagai suatu ciptaan utama—sebagaimana penciptaan manusia dalam tradisi Alkitabiah—yang kemudian terlibat dalam kehidupan. Arsitektur pertama-tama dipahami sebagai suatu objek yang dibuat. Dalam pembuatannya, arsitektur terwujud sebagai bentuk (form) dalam suatu proses yang terjalin dengan arsitektur sebagai benda fisik. Bentuk memiliki riwayatnya sendiri untuk terwujud secara aktif menjadi nyata melalui perwujudan bendawi arsitektur dalam proses perancangan. Di satu sisi seorang perancang mencipta bentuk, di sisi lain dia menjadikan bentuk yang telah ada atau bahkan asali sebelum dia mulai merancang menjadi nyata. Penciptaan bentuk dapat dipahami sebagai letting-be process atau menjadikan bentuk. Dalam pembuatan arsitektur sebagai perwujudan bentuk dengan menyusun material ada dua hal yang berperan sebagai modifying factors, yakni, teknik dan fungsi. Keduanya perlu untuk dipertimbangkan dalam penciptaan bentuk arsitektur menjadi nyata. Arsitektur, dengan demikian telah difungsikan dalam benak perancangnya sejak dalam proses penciptaannya dan dalam riwayat hidup bentuk yang melandasinya. Setelah arsitektur terwujud, pengguna akan melibatkan diri di dalamnya untuk mengalami (experiencing) arsitektur tersebut. Mengalami tidaklah sepenuhnya pasif sebagaimana membuat juga tak selamanya aktif. Sepanjang proses mengalami tersebut, pengguna melalui persepsi dan pengalamannya menjalin hubungan dan berusaha mengungkapkan bentuk bangunan. Setiap bangunan menjalin pengalaman 70 pragmatis, namun bangunan tertentu membangkitkan pengalaman estetis (aesthetic experience). Proses membuat arsitektur dan mengalami arsitektur dihubungkan oleh proses memahami arsitektur (understanding architecture). Apakah arsitektur mengungkapkan kebenaran ataukah arsitektur mengungkapkan keindahan adalah dua pertanyaan utama yang menantang dalam proses memahami arsitektur ini. Dalam tataran yang lebih mendasar, memahami arsitektur ini terkait dengan matra internal untuk memahami diri sendiri dan matra eksternal untuk memahami alam semesta. Proses membuat, mengalami dan memahami arsitektur dengan demikian dilakukan secara simultan oleh pembuat dan penggunanya. a) The Making of Architecture Membuat adalah suatu tindakan untuk menjadikan sesuatu ada, seniman menorehkan cat atau Tuhan bersabda mencipta. Bangunan atau ruang itu sendiri memiliki kehendak untuk mengada menjadi arsitektur, sehingga pembuat menjadikan nyata sesuatu yang telah memiliki hakekat keberadaan sebelum dia bertindak. Dalam pandangan Louis I. kahn dan Frank L. Wright yang hakiki ini adalah ruang (space) yang memiliki kehendak untuk mengada dan berupa kehampaan yang bermakna. Heidegger (2001) mengembangkan pemahaman filosofis terhadap sisi bendawi arsitektur, sebagai bangunan yang dihasilkan dari kegiatan membangun. Dengan argumen bahwa “mengada” (being) pada hakekatnya bersifat “keruangan” (spatial), Heidegger menekankan pentingnya manusia “berkediaman” (dwell) untuk mewujudkan keberadaannya di muka bumi. Berkediaman memiliki dua sisi: “memelihara” (cultivate) dan “membangun” (build). Memelihara berarti melestarikan dan menjaga suatu tempat yang diyakini mampu menjadi landasan manusia mengada. Memelihara dalam hal ini bisa dilakukan tanpa membuat apapun. Di sisi lain, membangun adalah mengkonstruksikan sesuatu secara bendawi. Penekanan terlalu dominan pada mengkonstruksikan acapkali menjadikan makna berkediaman menjadi kabur (Klassen, 1990: 21). 71 Membangun berkatian erat dengan berkediaman (to dwell) dan mengada (to exist). Membangun pada dasarnya adalah berkediaman (building is really dwelling), sedangkan berkediaman adalah cara manusia mapan di muka bumi. Berkediaman adalah cara manusia menyatakan keberadaannya dalam kaitannya dengan relasi “lipat empat” yakni: bumi atau lingkungan sekitarnya, langit atau jagad raya, manusia atau sesama dan Yang Ilahi. Membuat arsitektur, dengan demikian, memiliki dua proses yang berbeda yakni membuat objek fisis dan menjadikan sesuatu yang hakiki terwujud nyata yaitu keberadaan dengan relasi “lipat empat” tersebut. Bangunan dalam artian umum adalah produk fisis, yang akan menjadi arsitektur jika menyandang proses mengada dari yang hakiki. Dalam pembuatannya, arsitektur diwujudkan sebagai konstruksi melalui “techne” dan “poiesis”. Dalam bahasa Yunani, techne dipahami sebagai keterampilan atau kerajinan meskipun lebih tinggi dari sekedar keterampilan untuk pekerjaan kasar, bahkan kadang dianggap sebagai cabang pengetahuan praktis. Teknik ini diwariskan dan dikembangkan secara turun temurun sehingga memiliki prinsip-prinsip baku. Aristoteles mendefinisikan sebagai “kapasitas untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan pemahaman seacara tepat terhadap prinsip-prinsip terkait”. Techne yang menekankan pada teknik memproduksi dibedakan dengan “poiesis” yang bermakna mewujudkan. Klassen (1990: 22) mengungkapkan bahwa keduanya berkaitan dengan menjadikan sesuatu ada, meskipun techne lebih menkankan pada proses fisis sedangkan poiesis pada proses imajinatif. Konstruksi memiliki akar kata yang berarti menebarkan tapi sekaligus menyusun. Gambaran paling mudahnya adalah menyusun bata yang diawali dengan menebarkan bata menjadi suatu deretan dan kemudian menyusunnya dengan sebaran bata yang lain sehingga membentuk tumpukan, sebagaimana diyakini oleh arsitek Mies van de Rohe bahwa menyusun bata adalah tindakan yang paling esensial dalam mencipta arsitektur sebagai konstruksi atau baukunst. Istilah “arsitek” dipahami Klassen (1990: 22-23) berasal dari dua akar kata kata yakni “arkhein” yang bermakna memimpin dan mengatur dan “tekne” yang 72 menyusun, menjalin atau menganyam. Dengan demikian, arsitek berperan penting untuk menggagaskan dan mewujudkan gagasan tersebut dengan mengkoordinasikan para pekerja dan pengrajin lainnya. Arsitek, sebagaimana lazimnya dalam praktik sekarang, menuangkan gagasannya ke dalam gambar alih-alih berada terus menerus di tempat konstruksi untuk memberi perintah dan mengarahkan para pekerja agar membuat sesuai dengan gagasannya. Gambar menjadi medium antara gagasan—menjadikan yang abstrak di benak arsitek menjadi nyata di atas kertas—dan arahan di lapangan yang bukan hanya menunjukkan wujud jadi tapi juga mengungkapkan spesifikasi material, proses membangun dan sumber daya yang semestinya diperlukan. Dengan cara ini prinsip “firmitas” Vitruvius yang didasarkan pada pemilihan bahan bangunan dan metoda konstruksi sehingga bangunan dapat stabil (tidak roboh) dan awet (tidak lapuklekang) dapat terwujud. Bahan bangunan harganya mahal; menyusunnya sehingga menjadi bangunan juga tidaklah murah. Tak seperti pelukis yang dapat membeli sendiri bahan dan alat lukisnya untuk kemudian langsung berkarya, seorang arsitek memerlukan pihak pengguna yang memintanya untuk berkarya. Pengguna atau calon pengguna ini memiliki kebutuhan dan keinginan yang diharapkan dapat terpenuhi melalui bangunan yang dibuat oleh arsitek yang kadang sulit untuk diungkapkan sehingga menjadi tugas arsitek untuk menggalinya agar pengguna terpuaskan. Harapan pengguna ini di satu sisi berkaitan dengan aspek-aspek kenyamanan fisis untuk berada dan beraktivitas di dalam suatu bangunan. Di sisi lain, harapan ini berhubungan dengan citarasa estetika dan nilai-nilai luhur. Dengan pemosisian seperti itu, Klassen (1990: 24) memandang bahwa utilitas atau nilai guna sebagaimana diajukan oleh Vitruvius bersifat dwi-muka (Janus faced) yang menghubungkan antara firmitas yang bersifat material dan venustas yang bersifat non-material. Dengan demikan, urutan penyebutan oleh Vitruvius dengan meletakkan utilitas setelah firmitas dan sebelum venustas dapat dipahami, Karena sentralitas guna inilah, arsitektur mengalami periode kejayaan 73 aspek utilitas yang sering disebut sebagai Fungsionalisme. Dalam kerangka ini nilai penting slogan “form follows function” dapat dipahami. Dalam berkarya seorang arsitek kadang menjalin keseimbangan antara firmitas, utilitas dan venustas. Namun demikian, tak jarang pula dia memrioritaskan pemecahan masalah dari salah satu aspek tersebut sehingga lebih dominan ketimbang dua aspek yang lain. Meskipun karya seni seperti lukisan dan patung dibuat dengan penekanan pada aspek estetika, sejarah membuktikan bahwa hampir semua karya seni ketika dicipta menyandang nilai guna sebagaimana utilitas dalam arsitektur yang cukup penting. Karya seni untuk mengabadikan keagungan kuasa (sebagaimana di Mesir kuna), mengenang kejayaan seorang penakluk (sebagaimana di Romawi kuna) atau mendominasi lingkungan perkotaan (sebagaimana Eropa di masa Barok) adalah di antara contoh nilai guna dalam karya seni tersebut. Dengan memahami membuat arsitektur sebagai tindakan berganda, Klassen (1990: 26-27) memahami bentuk sebagai hasil dari membuat arsitektur juga dari dua aspek. Bentuk arsitektural yang bersifat bendawi dan teraga secara inderawi adalah aspek yang dapat dialami (experienced aspect) dari realitas arsitektural. Akan tetapi, bentuk juga memiliki aspek sebagai pengungkap makna yang merupakan kandungan (content) arsitektur. Terkait dengan pemahaman venustas sebagai kandungan utama arsitektur, Klassen menekankan pada pilihan terminologi venustas untuk keindahan yang bersifat luhur dan berkaitan dengan kedewaan ketimbang pulchrotido yang berarti kemolekan rupa semata. Keindahan arsitektural bersifat superfisial sekaligus mendalam lantaran keindahan ini serta merta dapat dilihat dan dinikmati dengan indera tapi juga mengungkapkan keluhuran dan kebenaran yang hanya dapat dihayati dengan rasa dan akal budi. Kalimat St. Agustinus dari Abad Pertengahan, “Keindahan adalah pancaran Kebenaran” menjadi landasan spiritual bagi cara pandang ini. Klassen (1990: 28) menengarai bahwa Vitruvius tak pernah mengeksplisitkan hubungan antara tiga serangkai sehingga dia menafsirkan venustas 74 disebut Vitruvius dalam urutan terakhir lantaran aspek ini didudukkan sebagai puncak kualitas arsitektur. Dengan argumen tersebut, Klassen memosisikan venustas sebagaimana terungkap dalam bentuk atau form sebagai bentuk yang merupakan tataran tertinggi arsitektur, sedangkan firmitas dan utilitas dikelompokkan sebagai modifiers of form yang berada dalam tataran yang lebih rendah. Dengan merujuk pada karya klasik Rapoport (1969), Klassen (1990: 28-29) berargumen bahwa kedua sisi bentuk yang diajukannya berkesesuaian dengan teori Rapoport tentang modifying factor. Aspek sosio-kultural yang mendudukkan bentuk sebagai perangkat simbolik adalah primary modifying factors, sedangkan aspek fisis seperti iklim, material, teknologi konstruksi dan metoda membangun adalah secondary modifying factors. Dalam memahami lebih lanjut tentang hubungan antara bentuk, fungsi dan teknik, Klassen (1990: 30-1) merujuk pada skema tiga dimensi yang dikembangkan oleh Charles Jencks dengan ketiga aspek arsitektur tersebut sebagai sumbu x, y dan z. Ternyata di antara arsitek terkemuka yang dibahas Jencks tak ada yang menduduki posisi seimbang dalam ketiganya. Jørn Utzon, Mies van de Rohe dan Phillip Johnson misalnya unggul dalam bentuk tapi memiliki skor sangat rendah dalam fungsi dan teknik. Sementara Pierre Nervi dan Buckminster Fuller sebaliknya memiliki skor yang luar biasa untuk aspek teknik tapi sangat rendah untuk bentuk dan fungsi. Kelihatan dari skema ini bahwa para arsitek tersebut tidak berusaha untuk menyeimbangkan ketiga aspek utama arsitektur tapi cenderung untuk menekankan salah satu di antara ketiganya. Bentuk arsitektural di Era Modern banyak dikaitkan dengan makna. Klassen (1990: 32-34) mengungkapkan bahwa manusia modern merasa teralienasi dari sesamanya, dari dunia dan dari Tuhannya sehingga berusaha untuk mencari makna, di antaranya melalui arsitektur. Eropa sejak masa Renaisans di abad ke-15 dan 16 membangun dunia yang berpusat pada manusia. Manusia berhasil menggeser citra Ilahi dan menggantinya dengan citranya sendiri. Namun demikian, lama kelamaan manusia yang mengagungkan dirinya sendiri dengan kekuatan akal budinya tersebut 75 menyadari banyak kekurangan dalam dirinya dan kesalahan yang dilakukannya. Ketika gambaran dirinya runtuh dan tak lagi bermakna untuk diungkapkan dalam arsitektur, manusia berupaya mencari hal lain yang hakiki. Sebagian manusia modern meyakini bahwa “ketiadaan” (nothing) adalah nilai mulia yang layak menggantikan keberadaan dirinya. Ketiadaan bukanlah kehampaan yang negatif melainkan suatu kekosongan yang luhur yang bahkan diyakini dapat dikaitkan dengan Tuhan dan manusia. Bermula dari Nietsche yang telah mempermaklumkan “kematian tuhan”, filsafat tentang ketiadaan dikembangkan oleh Heidegger yang dilanjutkan kemudian oleh Gadamer dan Derrida. Secara evolutif Derrida mengungkapkan bahwa arsitektur berawal dari sistem yang berpusat pada Tuhan yang kemudian beralih menjadi berpusat pada manusia. Pada akhirnya, arsitektur menjadi sistem yang merujuk pada dirinya sendiri tanpa menyandang makna selain yang berpangkal pada dirinya sendiri. Dengan merujuk pada perkembangan awal arsitektur di Eropa, Klassen (1990: 37-38) mengajukan argumen bahwa membuat arsitektur pada awalnya adalah mencipta ruang dalam dengan tujuan ritualistik. Jejak mula manusia melukisi permukaan dalam dinding gua Altamira dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan ritual, misalnya, adalah wujud nyata dari tindakan ini. Manusia menegaskan ruang dalam sebagai dunia yang terpisah dari lingkungan sekitarnya dengan membangun gerbang masuk ke dalam suatu bangunan sebagaimana masuk ke dalam suatu kota. Kota berisi banyak bangunan biasa dan bangunan yang memiliki nilai arsitektur. Merujuk pada Frampton, Klassen (1990: 39) membendakan antara bangunan biasa dan bangunan istimewa. Bangunan biasa lazimnya tak terlalu permanen, mudah digantikan dan acapkali tak ditujukan untuk melambangkan aspirasi atau nilai-nilai luhur. Bangunan seperti ini adalah hasil “kerja’ (labour) yang berbeda dengan arsitektur yang merupakan bangunan istimewa sebagai hasil “karya” (work). Sebagai bangunan yang dipentingkan, arsitektur lebih permanen dan di masa silam biasanya lebih besar. Arsitektur juga ditujukan untuk mengekspresikan nilai 76 luhur dan tujuan mulia suatu masyarakat. Namun demikian, Klassen menyatakan bahwa perbedaan antara bangunan biasa sebagai hasil kerja dan arsitektur sebagai hasil karya ini lebih baik dipandang sebagai ujung-ujung ekstrem suatu spektrum dengan sebagian besar bangunan di berbagai kisaran ranah abu-abunya ketimbang pembedaan dikotomis yang tegas. Di abad pertengahan, antara sosok katedral yang menjulang dengan rumah-rumah sederhana yang mirip satu sama lain dengan mudah dapat dibedakan. Akan tetapi di masa kini, suatu toko kecil di Wina dapat dirancang arsitek sekaliber Hans Hollein sedangkan pencakar langit yang mendominasi kota tak ada hubungannya dengan nilai luhur Keilahian tapi menunjukkan akumulasi kekayaaan semata. Menanggapi spektrum pembedaan tersebut, Klassen mengajukan argumen penting bahwa ada bangunan yang berbeda dari bangunan lain tetapi tidak terlalu menonjol. Namun demikian, bangunan ini memiliki kualitas tertentu yang menjadikannya berbeda dari bangunan kebanyakan. Kualitas ini tak mudah diungkapkan, sehingga secara filosofis Klassen (1990: 39) menyatakan bahwa bangunan ini “. . . has more form and meaning than the ordinary building because it has more being”. Ekses bentuk dan makna ini memungkinkan bangunan untuk berkomunikasi. Objek bersahaja menjadi penanda. Saat itu bangunan tersebut layak disebut sebagai arsitektur. Lebih dari sekedar ekses bentuk, bangunan tertentu memiliki keunggulan nilai estetika yang memancarkan keindahan sehingga berbeda secara mencolok dari bangunan lainnya. Dengan kualitas yang seperti ini maka bangunan tersebut dapat dipahami sebagai “Arsitektur” dalam arti yang sempit. Bangunan yang tidak memiliki bentuk yang menonjol, dalam argumen Klassen (h. 40) berikutnya, tetap dapat dikualifikasikan sebagai arsitektur dengan nilai keindahan yang berbeda. Dalam aspek teknik misalnya, suatu bangunan dapat dibuat dengan pilihan material yang unggul, pembuatan komponen bangunan yang seksama, penyambungan dengan kecermatan tinggi. Hal yang sama juga dapat dijumpai dalam aspek fungsional. Bangunan biasa ini 77 “Science is thought, but architecture is made”, Klassen (1990: 45) mengulang beberapa kali pernyataan ini. Dia menegaskan bahwa arsitektur adalah objek yang dibuat sambil menyatakan bahwa dalam membuat arsitektur, pemikiran tetap menduduki posisi yang penting. Klassen (1990: 53) mengakhiri bahasannya tentang membuat arsitektur dengan mengajukan sebuah paradoks. Dalam membuat arsitektur kita sepenuhnya berurusan dengan hal-hal nyata yang bersifat fisis dan bendawi. Namun demikan, hal yang ingin dicapai dari membuat arsitektur adalah makna, gagasan, estetika dan hal lainnya yang bersifat meta-fisis yakni yang melampaui realitas fisis. Paradoks inilah yang menjadikan kajian tentang membuat arsitektur akan selalu berkaitan dengan pertimbangan filosofis. Klassen (1990: 55) memahami bahwa bangunan adalah objek fisik yang ada di antara objek-objek yang lain dalam lingkungan. Karena kita tak dapat mengisolasi bangunan dari lingkungan sekitarnya, maka untuk dapat memahami suatu bangunan sebagai objek khusus kita perlu memperlakukan bangunan tersebut sebagai sosok (figure) dan lingkungan sekitarnya sebagai latar (ground). Dengan cara ini arsitektur sebagai suatu entitas menjadi keutuhan Gestalt (Gestalt whole). Gestalt adalah kajian psikologi untuk memahami kemampuan manusia dalam menerima dan membangun persepsi terhadap suatu entitas dalam dunia yang tampaknya tidak beraturan. Kajian ini menekankan pada suatu entitas secara holistik ketimbang semata sebagai jumlah dari unsur-unsur penyusunnya. Mengutip Perez-Gomez, Klassen menegaskan bahwa “the sphere of perception is the ultimate origin of essential meanings” (1990: 62). Dengan membangun persepsi yang komprehensif maka objek-objek yang didalami akan mengungkapkan makna yang ada dalam dirinya ke dalam kesadaran pengkajinya. Kemampuan mempersepsikan tersebut perlu dilatih melalui beberapa tahapan “bracketing”. Yang pertama adalah tahapan eidietic yang mereduksi keberadaan diri pengamat. Yang kedua adalah tahapan fenomenologis yang membebaskan objek dari pra-konsepsi dan kesadaran pengamat. 78 Klassen merumuskan lebih lanjut bahwa mempersepsikan adalah tahapan pertama mengalami keberadaan suatu objek. Dalam pandangan Merleau-Ponty, persepsi sepenuhnya dibangun melalui kehadiran tubuh yang mengindera lingkungannya. Tubuh menjadi agen bagi pengalaman dan pemahaman terhadap lingkungannya. Melalui persepsi ini dibangun imajinasi dalam diri pengamat. Objek estetis, misalnya, pertama-tama dia hadir untuk dapat dipersepsikan oleh tubuh pengamatnya. Imajinasi adalah internalisasi persepsi ke dalam diri pengamat. Merleau-Ponty menggambarkan relasi ini dengan menekankan bahwa objek itu sendiri dibuat dengan mengantisipasi [tubuh] pengamat yang akan melibatkan diri dengan objek yang diamati. Tahap ketiga atau yang terakhir dari mengalami adalah merefleksikan. Refleksi, di satu sisi bersifat kritis, mengambil jarak dengan yang diamati sehingga mampu untuk memberikan penilaian. Di sisi lain bersifat simpatis dengan melibatkan diri secara penuh dengan objek tersebut. Dalam refleksi kritis, pengamat mengakui keberadaan pembuat objek sehingga dia perlu untuk mengambil jarak untuk dapat memahaminya. Untuk itu dia berimajinasi sebagai pembuat yang aktif menciptakan objek tersebut. Dengan cara pandang ini Klassen menilai bahwa mengalami tidak sepenuhnya bersifat pasif lantaran melibatkan sisi pembuatan walaupun dalam tataran imajinatif (1990: 80). b) Experiencing Architecture Sebagaimana gubahan musik yang hanya menjadi nyata ketika diperdengarkan, maka arsitektur hanya menjadi nyata jika dialami. “When experienced, architecture is realized” (h. 52). Karena mengalami menjadikan arsitektur menjadi nyata maka mengalami bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat pasif dengan hanya menerima objek yang telah ada. Dalam proses mengalami arsitektur, pengguna bertindak selaku pembuat dengan mengambil peran secara kreatif yang semula disandang pembuat saat menciptakan arsitektur. Keduanya beralih peran (h. 54). 79 Mengalami diawali dan didasarkan pada persepsi. Untuk dapat mempersepsikan suatu objek dengan baik, pengamat perlu untuk mampu membedakan objek tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Bangunan atau arsitektur yang memiliki totalitas Gestalt dipandang sebagai sosok dengan lingkungan sekitarnya sebagai latar. Totalitas Gestalt ini terbentuk di antaranya melalui hukum integrasi, kedekatan (proximity), kesetaraan (equality), kesinambungan (continuity) dan kesederhanaan (simplicity). Setelah objek arsitektural dapat dipersepsikan sebagai entitas figuratif maka persepsi dapat mulai dibangun. Mempersepsikan ruang dengan kompleksitas riwayat ruang tersebut disebut Klassen sebagai “educated guess”. Pengamat melibatkan diri dengan objek tersebut untuk dapat mempersepsikannya secara fenomenologis. Heidegger menekankan pentingnya melampaui kesadaran individu dan menggali riwayat obek tersebut melampaui keberadaannya saat ini sehingga dapat memahami sejarah keberadaan objek tersebut sebagai proses mengada di dunia (being in the world). Marleau-Ponty, di sisi lain menekankan pentingnya raga sang pengamat dengan segenap sosok dan inderanya untuk dapat menjadi “agent of perception”. Dengan membangun sphere of perception secara baik kita dapat memahami makna yang hakiki atau essential meaning (Perez-Gomez, 1983). Mempersepsi dikembangkan menjadi mengalami. Klassen menekankan bahwa saat membuat arsitektur, sang pembuat sebenarnya sudah melakukan tindakan mempersepsikan dan mengalami tersebut sebagai suatu proses mental. Berdasar proses tersebut dia membuat dan menyempurnakan ciptaannya terus menerus sehingga dia terpuaskan (1990: 63). Ketika mengalami arsitektur, subjek secara langsung menjalin kontak ragawi dengan objeknya, yang dapat dibagi menjadi dua kategori yang saling berkaitan yakni menggunakannya (using) yang menghasilkan pengalaman praktikal atau memuliakannya (consecrating) yang menghasilkan pengalaman estetis. Keterlibatan dalam mengalami memiliki ragam jarak yang akan menghasilkan refleksi yang berbeda. Refleksi kritikal (critical reflection) terbantuk 80 ketika pengguna mengambil jarak dan memberikan penilaian terhadap objek yang dia geluti. Sementara, refleksi simpatik (sympathetic reflection) adalah hasil interaksi yang intim antara subjek dan objek sehingga sang subjek “berserah diri” ketimbang menghakimi objek tersebut (1990: 80). c) Understanding Architecture Memahami arsitektur menjadi perkara yang penting ketika arsitektur diyakini memiliki kebenaran yang hakiki di balik keberadaan bendawinya. Memahami adalah proses untuk mengungkap kebenaran (process to discover the truth). Pengungkapan kebenaran faktual yang kasat mata yang didasarkan pada aktivitas fisik (phronesis) didampingi dengan pengungkapan kebenaran yang tak kasat mata yang didasarkan pada aktivitas mental (sophia). Dengan pendekatan hermenutika fenomenologis, Klassen (1990) menyatakan bahwa kebenaran yang dikandung dalam arsitektur bukanlah kebenaran filosofis yang didasarkan pada korespondensi antara pemikiran dan realita ataupun berupa sistem gagasan yang koheren. Berdasar argumen Gadamer (1980) dia mengajukan bahwa kebenaran yang disandang arsitektur bukanlah gagasan abstrak yang terpisah dari realita arsitektur itu sendiri. Dengan demikian, fokus perhatian terpenting dari memahami arsitektur adalah “proper understanding of the truth” (Klassen, 1990: 93) melalui proses “aletheia” atau membiarkan tabir kebenaran tersingkap. Kebenaran sudah ada dalam objek itu sendiri yang akan terungkap melalui interaksi yang baik dengan subjek. Alih-alih kebenaran yang bersifat filosofis, kebenaran dalam arsitektur sebagaimana diyakini Klassen (1994 94) lebih dekat pada kebenaran sebagaimana terkandung dalam karya seni. Dalam karya seni, kebenaran dapat dialami (experienceable truth). Hal ini berkaitan dengan konsepsi tentang pengalaman total terhadap keberadaan dunia sebagaimana digagaskan oleh Heidegger (2001) dalam konsep Dasein-nya. Meskipun berakar pada totalitas pengalaman, kebenaran yang dapat dipahami dalam arsitektur memiliki dua sisi, yakni sophia yang berupa 81 pengetahuan teoretis (theoretical knowledge) dan phronesis atau kebenaran praktis (practical truth). Untuk dapat menyingkap kebenaran dalam arsitektur, Klassen mengembangkan gagasan-gagasan Gadamer, antara lain tentang seni sebagai permainan (art as play), peleburan cakrawala (fusion of horizons) dan bahasa sebagai mengada (language as being). Pemahaman, dalam konsep seni sebagai permainan, didasarkan pada interaksi antara subjek dan objek. Objek bukanlah entitas mandiri yang berhadapan dengan subjek untuk menerangkan keberadaannya sendiri. Objek ada dalam relasi timbal balik dengan subjek sebagaimana suatu permainan. Sebagai suatu permainan, karya seni memiliki aturannya sendiri yang tak sepenuhnya berada di bawah kendali pemainnya. Ketika arsitek Louis I. Kahn mengajukan pertanyaan hakiki tentang apa yang dikehendaki oleh ruang untuk mengada (what a space want to be) atau apa yang dikehendaki bata untuk mengada (what bricks want to be) maka sang arsitek melepaskan sebagian kewenangan kreatifnya untuk membiarkan sang ruang atau sang bata mendefiniskan tujuan keberadaan dirinya. Permainan mencapai kesempurnaannya jika dapat mewujud menjadi suatu seni sehingga mampu melebur subjek yang telah menjadi pemain ke dalam permainan itu sendiri (Klassen, 1990: 9597). Dalam moda pemahaman ini, prasangka (prejudice) tidaklah dipandang sebagai hal yang negatif. Prasangka adalah dugaan awal yang perlu untuk diajukan ketika seseorang akan terlibat dalam suatu pemahaman. Dugaan ini akan divalidasi sepanjang proses pemahaman sehingga dapat menyingkap kebenaran. Dengan memosisikan bahwa tak ada pemahaman yang sepenuhnya didasarkan pada kenaifan, ketika mengajukan prasangka, maka kita sedang membangun suatu cakrawala pandang (horizon) yang dari cakrawala itu kita akan mengembangkan pemahaman. Horison ini menyandang bias kesejarahan subjek yang penting diakui ketika melakukan upaya pemahaman. Prasangka yang diajukan dengan baik memungkinkan objek membentuk horisonnya sendiri yang berjarak dari horison sang pengamat. 82 Melalui permainan penafsiran yang intensif, kedua horison ini akan melebur. Pada saat itulah puncak pemahaman dapat dicapai (1990: 107-109). Dengan memosisikan bahwa kebenaran itu berbasis pada pengalaman (experienceable truth) ketimbang berbasis permenungan (reflective truth), Klassen (1990: 109-116) mendudukkan bahasa dalam posisi sentral untuk membangun pemahaman. Berbeda dengan peran bahasa sebagai instrumen dalam sistem simbol, dalam moda pemahaman ini bahasa berperan secara ontologis untuk mengada. Bahasa bukanlah alat representasi melainkan ungkapan keberadaan agar dapat dipahami, “Being that can be understood is language” (1990: 114). Klassen (1990:115) berargumen bahwa dalam bahasa inilah titik temu antara pendekatan hermeneutika sebagaimana diajukan oleh Gadamer dan fenomenologi sebagaimana diajukan oleh Norberg-Schulz dan Perez-Gomes terbentuk. Dengan memosisikan bahasa sebagai landasan membangun pemahaman, maka proses memahami bermula dari kata, untuk kemudian terlibat dalam realita yang ditujukan untuk membangun kandungan dan makna. Mengingat peran sentral bahasa dalam pemahaman teks, maka dalam pemahaman arsitektur mestinya didasrkan juga pada “bahasa arsitektur” (language of architecture) (1990: 118). Alih-alih bersifat metaforikal ataupun representasional, bahasa dalam hal ini adalah realitas itu sendiri. Klassen tidak membahas lebih jauh tentang bahasa arsitektur yang dipahaminya berbeda dengan yang diungkapkan dalam pendekatan linguistik dan semiotika. Klassen mengakhiri diskusinya tentang memahami arsitektur dengan mempertentangkan antara Regionalisme Kritis sebagaimana diajukan oleh Kenneth Frampton dan Postmodern Kitsch sebagaimana dikembangkan oleh Robert Venturi. Regionalisme Kritis mengajukan pemahaman baru yang otentik yang menyandang universalitas sekaligus lokalitas. Sementara, Postmodern Kitsch menoleransi kepurapuraan. Dengan mengutip Dimitri Porphyrios, dia berargumen bahwa kitsch membuat simulasi untuk menutupi ketiadaan, sedangkan seni mengimitasi untuk membangun 83 jarak dengan yang ada. Pemahaman yang baik haruslah mampu mebedakan antara keduanya. d) Proses Arsitektur dan Ketidak-panggahan Cara pandang Klassen yang bertolak dari paradigma penciptaan karya seni, seperti lukisan dan komposisi musik, sekaligus mengkritisi cara pandang tersebut. Pencipta adalah pihak yang berbeda dengan penikmat karya seni. Pencipta aktif membuat dan menggubah karya, sementara penikmat mengalami atau menghayati karya seni tersebut secara pasif. Dengan mengembangkan teori Proses Arsitektur, Klassen berargumen bahwa dalam keterlibatan manusia dengan arsitektur meliputi aktivitas mental dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dipahaminya sama dengan pemahaman konvensional yang mendudukkan arsitek sebagai pelaku aktif dan pengguna sebagai pelaku pasif. Dalam aktivitas mental, pembuat dan pengguna berbaur dan bertukar peran. Membuat arsitektur tak sepenuhnya bersifat aktif lantaran pembuat atau arsitek hanya mengungkapkan bentuk yang sudah ada dalam khasanah kultural sebelumnya. Sebaliknya, dalam mengalami arsitektur pengguna mencipta dalam benaknya. Untuk dapat memahami penciptaan berulang seperti di Trusmi, pendekatan prosesual ini potensial untuk diterapkan dengan membuka kemungkinan baru yakni: • Proses pembuatan berulang bukan hanya terjadi sebagai aktivitas mental tapi juga merupakan aktivitas fisik • Pembuat dan pengguna dalam proses ini tidak selalu pihak yang berbeda. Pembuat dapat berperan sebagai pengguna dan sebaliknya baik secara fisik maupun secara mental. 2.3.2. Landasan Teori: Teori The Presence of Architecture Norberg-Schulz Norberg-Schulz (1963, 1980) mulai mengembangkan teorinya tentang arsitektur dengan latar belakang situasi Eropa pasca Perang Dunia II. Pembangunan 84 masif dan agresif di banyak kota untuk memenuhi kebutuhan hunian dipenuhi dengan sistem produksi industrial yang memungkinkan pembuatan bangunan-bangunan terstandardisasi secara cepat. Meskipun telah memenuhi kriteria produk yang dirumuskan dengan baik, bangunan yang dihasilkan tak memberikan kepuasan sebagaimana dimiliki bangunan masa silam yang menurutnya lebih bermakna. Untuk mendapatkan jawaban tentang “berkediaman yang bermakna”, Norberg-Schulz banyak merujuk pada cara pandang Heidegger (2001) tentang realitas bendawi atau “the thing” yang bermakna yang dibedakannya dari “the object” yang berupa wujud fisik semata. Menggali makna adalah perkara yang rumit dalam realtas non-verbal seperti arsitektur. Norberg-Schulz membangun teorinya tentang kediaman bermakna (meaningful dwelling) dengan berlandaskan pada prinsip bahwa: 1) keberadaan manusia itu pada dasarnya bersifat keruangan (spatial existence), dan 2) ruang yang mewujudkan eksistensi tersebut bukanlah entitas yang abstrak sebagaimana dipahami para ilmuwan tetapi bersifat nyata dan khas pada suatu bentang lansekap tertentu (Norberg-Schulz, 1980, 1985, 2000). Setiap tempat yang nyata dan diyakini bermakna oleh penggunanya, dalam paradigma Norberg-Schulz, memiliki karakteristik yang asasi atau ruh yang disebutnya sebagai genius loci. Peran terpenting arsitektur adalah membuat genius loci tersebut menjadi nyata sehingga hadir dalam eksistensi suatu tempat (NorbergSchulz, 1980). Dalam kaitannya dengan tempat keberadaannya, arsitektur sebagai perwujudan dari genius loci memiliki karakteristik berganda. Di satu sisi, arsitektur mengungkapkan ciri-ciri tempat tersebut yang merupakan jalinan antara karakteristik bentang alami dan lingkungan buatan manusia. Di sisi lain, arsitektur mengungkapkan karakteristik umum sebagai objek yang berdiri di muka bumi dan di bawah naungan langit (Norberg-Schulz, 1980). Realitas konkret ini memiliki empat cara untuk mengungkapkan tempat kedudukan eksistensial yang disebutnya sebagai modes of dwelling yang meliputi (Norberg-Schulz, 1985): 85 a) kediaman alami atau natural dwelling yang berupa bentang alam yang ditransformasikan menjadi permukiman, b) kediaman kolektif atau collective dwelling yang terwujud dalam ruang urban, c) kediaman publik atau public dwelling yang diwujudkan dalam bangunan publik dan kelembagaan, dan d) kediaman pribadi atau private dwelling yang berupa rumah tinggal. Dalam kajiannya tentang berbagai ragam paradigma fenomenologi dalam mengkaji arsitektur, Shirazi (2014) menyebut Norberg-Schulz sebagai pelopor “phenomenology from without” yang menekankan pada keberadaan suatu objek arsitektural pada suatu lingkungan tertentu sehingga kadang disebut juga sebagai fenomenologi yang berbasis tempat. Norberg-Schulz berargumen bahwa karakter arsitektural berkembang dari pemahaman secara dinamis dan terus menerus antara upaya manusia untuk berkediaman (to dwell) dan tempat yang dipilihnya untuk berkediaman sehingga membentuk muka bumi yang dihuni (inhabited landscape). Dia menyebut lingkungan kediaman ini sebagai ranah kehidupan world of life yang terbentuk dari relasi antara ranah alam atau world of nature dan ranah manusia atau world of men. Kehadiran arsitektur untuk membentuk tempat yang bermakna ini memiliki tiga aspek, yakni guna (use), pemahaman (comprehension) dan penerapan (implementation). Guna adalah tidakan fundamental yang dilakukan untuk menyatakan keberadaan seseorang di suatu tempat yang meliputi, antara lain, kedatangan (arrival), perjumpaan (encounter), berespakat (agreeing). Kesemua guna tersebut bersama-sama mewujudkan tindakan berkediaman (to dwell). Pemahaman bersifat kualitatif dan menyeluruh sehingga mampu memaparkan karakteristik umum tempat yang bermakna dan karakteristik khusus tempat tersebut. Penerapan adalah proses mentransformasikan lansekap yang dipahami menjadi lansekap yang dihuni melalui penerapan pemahaman menyeluruh tersebut. 86 a) Guna Guna merupakan upaya manusia membangun tempat sebagi kediaman secara bermakna dalam berbagai skala dan moda. Suatu tempat memiliki karakteristik kualitatif yang utuh yang mebedakannya dengan bentang alam di sekitarnya. Tempat ini dibangun untuk merealisasikan guna yang fundamental. Dengan rasa memiliki suatu tempat, seseorang mengembangkan identitas diri dan tempat tersebut yang dpahami Norberg-Schulz terdiri atas karakteristik tempat dan karakteristik komunitas (2000: 33). Dengan hadir di suatu ruang yang memiliki kualitas sebagai tempat, seseorang mengawali menyatakan “kehadirannya” di tempat tersebut. Kehadiran berkembang menjadi “perjumpaan” yang akan membawanya menuju “pertemuan” (meeting) dengan banyak pihak. Dalam pertemuan ini dikembangkanlah berbagai kemungkinan untuk berkediaman yang mungkin akan diikuti dengan “kesepakatan” antar pihak tersebut. Kediaman yang kemudian terbentuk dan mampu bertahan dari waktu ke waktu karena memiliki struktur mendasar (fundamental structure). Struktur fundamental ini didasarkan pada memori, orientasi dan identifikasi (Norberg-Schulz, 2000: 42-46). Memori berperan dalam membantu pengguna mengenali lingkungan berdasarkan pada khasanah karakter suatu tempat yang dimiliki oleh penggunanya. Orientasi memberi arah bagi pengguna untuk bergerak dan mengembangkan ruangnya secara horisontal, sedangkan Identifikasi menjadikan tempat memiliki wujudnya yang konkret secara vertikal. Ketiga komponen struktur fundamental tersebut terwujud nyata dalam aspek-aspek keberadaan yang berupa sosok (figure), bentuk (form) dan ruang (space). Memori membentuk karakter terhimpun sehingga tempat kediaman dapat dikenali sebagai suatu sosok. Orientasi yang bersifat ekspansif terwujud dalam suatu ruang; sedangkan identifikasi terbangun sebagai bentuk. Agar suatu tempat dapat dikenali dan dipahami dengan baik haruslah memiliki identitas yang didasarkan pada permanensi. Norberg-Schulz (h. 54) 87 merumuskan bahwa permanensi yang dimaksud bukanlah keawetan dan ketangguhan suatu benda melainkan praktik membangun tertentu yang dilakukan secara terus menerus pada suatu tempat. b) Pemahaman Dalam paparan teoretiknya, Norberg-Schulz (2000) menggunakan istilah “comprehension” dan “understanding” secara bergantian untuk mengungkapkan gagasan tentang pemahaman. Hal yang fundamental dalam memahami arsitektur adalah kemampuan untuk mengungkapkan arsitektur sebagai suatu keseluruhan yang bersifat kualitatif (qualitative whole) yang tak tereduksi sebagaimana dalam abstraksi rasional. Keseluruhan ini menyandang sifat berganda. Di satu sisi entitas ini memiliki karakteristik universal sebagaimana dimiliki oleh keseluruhan yang setara di manapun juga. Di sisi lain, entitas ini memiliki karakteristik yang khas khususnya yang berkaitan dengan tempat yang akan membedakannya dari entitas lain dan dari lingkungan sekitarnya. Secara filosofis dia mengaitkan sifat berganda ini dengan transedentalisme Plato dan imanensi Aristoteles sehingga setiap rumah memiliki sifat asasi “ke-rumah-an” yang universal sekaligus manifestasinya secara konkret sebagai suatu rumah yang berbeda secara kualitatif dari rumah yang lain. Dalam pandangan Heidegger, hal ini dikembangkan menjadi prinsip “being” yang universal dan “manifestation of being” yang partikular. Dalam merumuskan nilai universal dalam tiap kediaman yang bermakna, Norberg-Schulz merujuk pada paradigma Heidegger tentang “kediaman Empat Serangkai” (the fourfold dwelling, quadrature atau das geviert). Dalam paradigma ini suatu kediaman menyandang relasi antara bumi—langit dan antara makhluk—yang ilahi (heaven—earth dan mortals—divine) (Mitchell, 2015). Nilai-nilai ini mewujud secara partikular dalam tiap kediaman yang ada di tempat yang berbeda. Langit tropika dengan busur lintasan matahari yang terentang dari ufuk barat dan timur, misalnya, menjalin hubungan dengan cara yang berbeda dengan bentang alam gurun dengan cakrawala yang terentang dan dengan lembah hijau yang curam. 88 Antara karakteristik yang bersifat partikular dan universal terdapat relasi pencerminan (mirroring). Dari relasi tersebut terbantuklah citra dunia (images of the world) yang bersifat partikular tapi menyandang nilai universal. c) Penerapan Penerapan atau implementasi didefinisikan Norberg-Schulz (2000: 91-92) sebagai “building the world of life based on understanding of place” atau “translating the landscape that has been understood into architecture”. Dalam definisi ini pemahaman terhadap karakteristik lingkungan yang dijumpai berperan sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang akan diimplementasikan dalam lingkungan tersebut. Norberg-Schulz memberikan gambaran tentang beragam langgam yang berbasis pada cara pandang yang berkembang pada suatu masa tertentu, khususnya di Eropa yang memberikan karakteristik khas pada implementasi ini. Rasionalime di masa Renaisans yang mengidealkan kesempurnaan dalam kesederhanaan bentuk mengembangkan wujud yang berbeda dengan cara pandang absolutisme masa Barok yang mementingkan totalitas ketimbang elemen-elemen penyusunnya. 2.3.3. Ringkasan Teori Secara ringkas kedua teori tersebut dapat disndingkan komponen- komponennya sebagaimana berikut: 89 Tabel 2.1. Ringkasan Landasan Teori MAKING ARCHITECTURE • Proses yang bersifat “let it be” • Terdiri atas “aktivitas fisik” dan “aktivitas mental” • “Aktivitas Mental” bersifat kontinyu dan dapat diperankan oleh pengguna EXPERIENCING ARCHITECTURE • Melengkapi proses membuat karena pembuatan arsitektur baru lengkap setelah dialami • Terdiri atas persepsimengalami-refleksi • Refleksi dapat bersifat kritis atau simpatik UNDERSTANDING ARCHITECTURE • Proses mengungkap kebenaran dalam arsitektur • Meliputi kebenaran ilmiah (sophia) dan kebenaran praktikal (phronesis) IMPLEMENTATION The Presence world of of Architecture • Membentuk life=world of (Norbergnature+world of men Schulz, 2000) • Merealisasikan USE • Terdiri atas “tindakan primordial” dan “momen penggunaan” • Tindakan primordial (tiba, berjumpa, bersepakat dsb.) melandasi pembentukan tempat berkediaman dalam jangka panjang COMPREHENSION • Memahami tindak berkediaman sehingga kediaman menjadi understood landscape. • Memahami arsitektur/kediaman sebagai “qualitative whole” • Membentuk pemahaman terhadap arsitektur sebagai “Empat Serangkai” The Process of Architecture (Klassen, 1990) “Empat Serangkai” menjadi nyata dalam struktur formal, yakni: tipologi, topologi dan morfologi 90 BAB 3 METODA KAJIAN Ketidak-panggahan yang terwujud dan dikembangkan di lingkungan Kramat Buyut Trusmi telah berjalan dalam jangka waktu yang lama, melibatkan warga dan masyarakat secara luas, serta terjalin dalam berbagai aspek kehidupan di tempat tersebut. Lingkungan binaan dan praktik berarsitektur di Kramat Trusmi terkait dalam suatu jalinan dalam Kajian tentang ketidakpanggahan dalam arsitektur ini disusun sebagai suatu bentuk pengembangan teori melalui pendalaman terhadap suatu tempat dan praktik yang diselenggarakan di dalamnya. Berdasar kerangka kajian tersebut maka penyusunan metoda kajian didasarkan pada karakteristik teori yang dikembangkan serta karakteristik tempat dan praktik yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini mengangkat tempat dan praktik berarsitektur di Kramat Buyut Trusmi sebagai suatu kasus untuk dikaji secara komprehensif. Sebagai kajian terhadap suatu keutuhan dalam lingkup tertentu, penelitian ini cenderung berkarakter kualitatif. Creswell (2007) mendefinisikan karakteristik penelitian kualitatif sebagai “the investigator explores a bounded system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time, through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information.” Keunikan Kramat Buyut Trusmi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya menjadikan tempat ini bisa diperlakukan sebagai suatu “bounded system” untuk dilakukan investigasi secara mendalam. Lebih lanjut, Creswell memaparkan bahwa suatu penelitian studi kasus dapat ditujukan untuk mendalami objek tersebut secara khusus atau mengaitkan dengan teori yang sudah ada. 91 Dalam hal ini, penelitian tentang Kramat Trusmi ini ditujukan untuk mengembangkan teori. Untuk itu, peneliti melakukan pendalaman teori sebagai latar pengetahuan sebelum melibatkan diri dengan obeservasi di lapangan. Metoda penelitian lebih lanjut dirumuskan melalui pendalaman karakteristik objek yang dikaji dan karakteristik teori yang dikembangkan. 3.1 Karakteristik Objek: Ketidak-panggahan dalam Arsitektur Kramat Buyut Trusmi Kramat Buyut Trusmi sendiri adalah suatu lingkungan binaan dengan karakteristik fisik dan praktik yang khas. Secara fisik, Kramat ini terdiri atas lebih dari 20 bangunan beratap sirap dan alang-alang yang didirikan berdempetan satu sama lain. Keseluruhan kompleks ini dikelilingi oleh pagar pasangan bata setinggi mata yang memisahkan secara visual dengan lingkungan sekitarnya meskipun secara spasial tetap terhubung karena kedua gerbangnya tak pernah tutup sepanjang tahun. Kompleks yang terletak di tengah Desa Trusmi ini diyakini masyarakat setempat sebagai situs cikal bakal permukiman mereka yang telah dikembangkan lebih dari 400 tahun yang lalu dan tempat mengebumikan tokoh pendiri Desa tersebut. Sepanjang tahun peziarah dari berbagai penjuru hingga sejauh lebih dari 100 kilometer datang ke tempat ini untuk berbagai kepentingan. Prosesi rutin mengganti atap sirap dan alang-alang di Kramat Buyut Trusmi yang menjadi fokus utama kajian ini diselenggarakan secara ritualisti yang melibatkan ribuan partisipan. Masyarakat setempat memahami tradisi ini telah berlangsung sejak awal Desa mereka berdiri. Dengan sifat ritualistik, partisipasi ekstensif dan penyelenggaraan yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, tradisi penggantian atap tersebut tidak dapat dipandang sebagai langkah teknis untuk memperbaiki atap semata namun memiliki muatan simbolis dan kultural yang sangat kuat. Untuk memahami tempat, arsitektur dan tradisi yang menyertainya ini diperlukan strategi yang bersifat kualitatif dan komprehensif menyangkut berbagai dimensi kehidupan masyarakat. 92 3.2 Karakteristik Teori: Klassen dan Norberg-Schulz Norberg-Schulz menulis serangkaian kajian teori arsitektur yang berkaitan satu sama lain walaupun tidak merupakan suatu serial tapi didasari oleh paradigma yang sama. Tulisan-tulisan tersebut memiliki latar pendekatan fenomenologi yang sangat kuat yang menjembatani berbagai tema kajian yang didalaminya. Di antara tema kajian yang paling menonjol dalam karya-karya Norberg-Schulz adalah: a) Ruang Eksistensial. Kajian bertema Ruang Eksistensial ini menekankan pada pemahaman bahwa “being” pada dasarnya bersifat spasial yang dijabarkannya sebagai “develop the idea that architectural space may be understood as a concretization of environmental schemata or images, which form a necessary part of man’s general orientation or ‘being in the world” (Norberg-Schulz, 1971). Tema ini terutama dikembangkan dalam bukunya Existence, Space and Architecture (1971) yang menandai pergeseran paradigmanya dari strukturalisme dan semiotika menjadi fenomenologi. b) Fenomenologi Tempat. Dalam bukunya Genius Loci: Towards the Phenomenology of Architecture (1981) Norberg-Schulz menekankan keberadaan eksistensial tersebut dikembangkan dalam relasi intensif antara manusia dan lingkungan yang dibentuknya. Dalam relasi ini suatu tempat akan memiliki jiwa yang bertahan dalam jangka panjang yang terungkap dalam lingkungan binaan yang secara gradual terbentuk. Jiwa tempat yang aktif inilah yang disebutnya sebagai Genius Loci. c) Konsep tentang Kediaman. Mapan secara bermakna pada suatu tempat disebut Heidegger (1951) sebagai dwelling atau berkediaman. NorbergSchulz mengembangkan secara komprehensif tema berkediaman ini dalam berbagai level dan berbagai konteks. 93 Buku terakhir Norberg-Schulz (2000) Architecture: Presence, Language and Style dapat dipandang sebagai upayanya untuk merangkaikan berbagai teori, konsep dan gagasannya yang berlatar filsafat fenomenologi tersebut. Dalam buku ini dia menekankan keberadaan arsitektur sebagai qualitative whole atau keutuhan kualitatif yang bermakna sebagai world of life atau lingkungan berkehidupan yang dikembangkan dari penggabungan antara world of nature antara lingkungan alam dan world of man atau lingkungan buatan manusia. Klassen (1990) menjuduli bukunya dengan pendekatan yang dikembangkannya, Architecture and Philosophy: Phenomenology, Hermeneutics and Deconstruction. Klassen tidak banyak menulis yang bersifat normatif tentang objek arsitekur itu sendiri, dan lebih menekuni pada proses mempersepsikan, memikirkan dan merfleksikan. Dia menyebut rangkaian ini sebagai “The Process of Atchitecture” mengawali rangkaian ini dengan “membuat arsitektur” dan mengakhiri dengan “memahami arsitektur”, di antara keduanya terdapat “mengalami arsitektur” yang disebutnya sebagai bermuka ganda menjambatani antara membuat dan memahami. Untuk mempersepsikan dan menginternalisasikan persepsi tersebut, Klassen banyak merujuk pada prosedur fenomenologi. Lebih lanjut, dia mengembangkan pendekatan hermeneutika, khususnya yang didasarkan pada teori-teori Hans Georg Gadamer, sebagai prosedur untuk menafsirkan fenomena. Sedangkan untuk mengkritisi penafsiran tersebut Klassen mengembangkan pendekatan dekonstruksi. 3.3 Strategi Penelitian Kualitatif Ketidak-panggahan dalam arsitektur Kramat Buyut Trusmi bersifat multi dimensional dengan interaksi antar-dimensi yang sangat intensif. Peristiwa penggantian dan pemindahan komponen bangunan tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan dimensi teknis, ritual maupun sosial. Masing-masing dimensi dapat didalami namun memerlukan penjelasan dari dimensi yang lain untuk dapat membangun pemahaman komprehensif. 94 Groat dan Wang (2013) menyarankan kajian dengan dimensi yang kompleks dan keterkaitan dengan tempat asal yang tinggi untuk menggunakan strategi penelitian kualitatif. Strategi ini memungkinkan berbagai dimensi tersebut dapat dipahami kesalingterkaitannya guna menafsirkan gagasan-gagasan mendasar dalam lingkungan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen sentral dengan interaksi yang tinggi antara peneliti dan hal yang diteliti. Lebih lanjut di antara karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana dirumuskan oleh Groat dan Wang (2013) yang relevan dengan kajian arsitektur Kramat Buyut Trusmi adalah sebagai berikut: a) Penekanan pada setting alami. Penelitian kualitatif menekankan pada hal yang bersifat khas yang berkaitan erat dengan lingungan aslinya. Sebagai lingkungan cikal bakal, Kramat Buyut Trusmi bukan hanya berkaitan dengan desa dan permukiman di sekitarnya tapi bahkan menjadi asal muasal tempat tersebut. Sepanjang riwayatnya, Kramat ini juga selalu diposisikan sebagai “jantung” spiritual kehidupan warga dengan terus menerus menyelenggarakan ziarah, ritual, perawatan dan pembangunan kompleks ini. b) Berfokus pada penafsiran dan makna Informasi yang beragam dan komprehensif memerlukan strategi penafsiran sebagai upaya untuk membangun makna dari hal yang dikaji. Investigasi komprehensif dan mendalam untuk menghimpun berbagai informasi serta pengembangan skill penafsiran untuk mengaitkan satu informasi dengan informasi yang lain adalah kunci untuk dapat mengungkapkan makna dari fenomena setempat yang diamati. Di antara bermacam ragam informasi yang saling berkait di Trusmi adalah tentang lingkungan fisik dalam berbagai level (desa, kompleks, bangunan dan bagian bangunan); lingkungan sosial dengan dinamikan serta berbagai peran dan afiliasi warga; serta prosesi ritual dengan tatacara serta pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan material dan teknik untuk merangkaikannya. c) Berfokus pada cara responden memaknai lingkungannya 95 Kramat Buyut Trusmi dan Desa Trusmi memiliki kekhasan fenomena tapi sekaligus keragaman cara warga setempat memaknainya. Warga dan pemuka desa memiliki keragaman yang kaya dan bahkan kadang bertentangan satu sama lain untuk penamaan suatu bangunan, pemaparan alur kesejarahan atau penjelasan tentang rinci dan lambang pada suatu komponen upacara, serta berbagai fitur tradisi lainnya. Strategi Kualitatif ini menekankan pada upaya untuk menghimpun beragam informasi tersebut sebagai landasan untuk membangun makna melalui penafsiran yang inklusif. d) Penggunaan beragam taktik Dengan jenis informasi yang beragam, penelitian kualitatif memerlukan taktik yang beragam juga untuk menghimpun informasi, menyajikannya dan menafsirkannya. Pencatatan dan pemotretan peristiwa pembangunan dan ritual di Kramat Trusmi sangat membantu untuk membangun pemaparan mendalam tentang makna membangun dan mendaur ulangkan komponen bangunan. Untuk memahami relasi antar tokoh, peristiwa di masa silam dan gagasan-gagasan kultural diperlukan perbincangan mendalam dengan berbagai kalangan di Desa Trusmi. Melibatkan diri dalam kehidupan keseharian dan peristiwa ritualistik memberi gambaran tentang arti penting peristiwa tersebut dalam kehidupan masyarakat. 3.4 Pendekatan Fenomenologi dan Hermeneutika Di antara ketujuh strategi penelitian yang diajukan oleh Groat dan Wang (2013), strategi penelitian kualitatif adalah yang paling luas dengan keragaman tertinggi. Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan beberpa alternatif pendekatan. Namun demikian, pendekatan fenomenologi memiliki landasan filosofis yang paling sahih (Wang dan Groat, 2013). Fenomenologi meliputi kisaran yang luas dengan pemahaman secara beragam. Shirazi (2010) memaparkan bahwa status dan definisi yang beragam tersebut meliputi antara lain: Edmund Husserl memahaminya sebagai “kembali ke hakikat benda”, Martin Heidegger memahaminya sebagai “metoda” atau “cara pandang”, Maurice Merleau-Ponty memahaminya sebagai 96 “hakikat persepsi”, sedangkan Dermott Moran memandangnya sebagai “praktik ketimbang sistem”. Lebih lanjut, Seamon (2000) memilah fenomenologi dalam kajian arsitektur menjadi tiga kecenderungan alur, yakni: a) Hermeneutical, dalam alur hermeneutika pengkaji melibatkan pengalaman dan menjalinnya dengan pengetahuan lainnya yang terkait dengan pengalaman tersebut sebagai upaya untuk membangun penafsiran yang komprehensif. b) First person, dalam alur ini pengkaji mengerahkan sepenuhnya kemampuan inderawinya untuk membangun pemahaman. Tubuh menjadi instrumen utama untuk membangun pengetahuan. Pengetahuan yang telah dimiliki pengkaji sebelumnya dibatasi untuk terlibat dalam pemaknaan pengalaman ini. c) Existensial, serupa dengan alur kedua dengan fokus pada “the specific experiences of specific individuals or groups in actual situations or places”. Paparan individual didiskusikan secara mendalam dengan pihak lain sehingga terbentuk pemahaman bersama. Berdasar karakteristik teori yang akan dikembangkan dan kasus yang dikaji maka alur fenomenologi hermeneutika adalah yang paling relevan. Kekuatan alur ini adalah dalam kemampuannya mengintegrasikan antara pengalaman dan penafsiran sehingga dapat menjadi sarana pembentukan dan pengembangan teori. Secara eksplisit Seamon (2000) menyebut Norberg-Schulz memiliki kecenderungan dalam alur ini, sementara Klassen (1990) dengan tegas menyatakan bahwa dia menggabungkan antara fenomenologi dan hermeneutika. Filsuf Paul Ricoeur memelopori pengembangan keterkaitan antara fenomenologi dan hermeneutika pada paruh pertama abad ke-20 (Davidson dan Valée, 2016). Pengaitan ini pertama-tama ditujukan untuk mengkritisi fenomenologi berbasis pengalaman ego murni yang terlepas dari semua konteks sebagaimana diajukan oleh Edmund Husserl. 97 Ricoeur (1971) lebih lanjut mengembangkan model pemahaman “tindakan bermakna yang diperlakukan sebagai teks” (meaningful action considered as text). Untuk itu dia mengajukan sejumlah kriteria agar suatu tindakan dapat ditafsirkan sebagaimana suatu teks, antara lain: kemapanan tindakan, otonomi tindakan dan relevansi tindakan. Dalam mengembangkan kajian kualitatif tentang arsitektur, Seamon (2017) mengajukan pembandingan sekaligus pengaitan antara fenomenologi dan hermeneutika dalam hal tujuan, tema dan metoda. Dalam kajian arsitektur, fenomenologi bertujuan mengembangkan pengetahuan tentang pengalaman (experience) manusia terhadap suatu lingkungan binaan secara akurat dan komprehensif; sedangkan hermeneutika bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang pemaknaan (meaning) manusia terhadap suatu lingkungan binaan secara akurat dan komprehensif. Dalam ranah fenomenologi, lingkungan binaan diperlakukan sebagai tempat sehingga dipahami dengan mengalami dan melibatkan diri dalam kehidupan di tempat tersebut. Dalam ranah hermeneutika, lingkungan binaan diibaratkan sebagai suatu teks yang membentuk dan menyampaikan makna yang dipahami dengan penafsiran intensif dari berbagai sudut pandang. Kedua pendekatan ini saling melengkapi karena menurutnya “experience and meaning often overlap and intermingle experientially and interpretively” (Seamon, 2017, 138). Strategi untuk menggabungkan fenomenologi dan hermeneutika, di antaranya diajukan oleh Bourdieu (1990) dalam kajiannya tentang rumah Kabyle di kalangan Suku Berber di Aljazair. Dalam kajian tersebut, dia mengibaratkan rumah sebagai sebuah buku yang berisi konstruksi dan pemahaman kultural suku tersebut. Buku yang bersifat non-verbal ini “dibaca” dan “dipelajari” dengan pengalaman ragawi penghuninya. Ketika seseorang memasuki ruang dalam rumah maka dia memosisikan seisi rumah tersebut berdasar tubuhnya (kiri-kanan, muka-belakang) serta alam semesta (matahari terbit-matahari terbenam). Pemahaman yang bersifat subjektif mendapatkan objektifikasinya dalam pengalaman ruang, dan sebaliknya. 98 Lebih dari sebatas “membaca” melalui pemanfaatan ruang sebagaimana digambarkan oleh Bourdieu, warga Trusmi juga “menulis” secara terus menerus. Warga Trusmi, dalam lingkup yang luas, bukan hanya terlibat dalam pemanfaatan ruang dan bangunan tapi juga pembuatan keduanya. Dengan membuat bangunan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, mereka “menuliskan ulang” pembelajaran tersebut. Di satu sisi “penulisan ulang” ini semakin menegaskan pesan yang diungkapkan, akan tetapi juga membuka peluang bagi “modifikasi” dalam berbagi levelnya. Lebih lanjut Seamon (2017) memaparkan bahwa fenomenologi dan hermeneutika memiliki keserupaan tematis, yakni memiliki empati yang tinggi terhadap hal yang dikaji tetapi juga berupaya untuk menyajikan, memaparkan dan memahami untuk kalangan yang luas. Secara metodologis, validitas kedua metoda kajian tersebut didasarkan pada: • Keserbacakupan (comprehensiveness) dengan melibatkan pengalaamn dan bukti yang luas dalam berbagai aspek • Kedalaman pemaknaan (semantic depth) yang mampu menjelaskan hal yang dikaji dalam jangka waktu yang lama dan lingkup yang luas. • Keterlibatan (inclusivity) dengan kajian yang memiliki lingkup yang semestinya sehingga tema kajian dapat dipahami dengan baik, • Struktur arsitektonis (architectonic structure) dengan makna atau pengalaman dapat dikaitkan dengan lingkup yang lebih luas dari fenomena asalnya. 3.5 Metoda Kajian Sebagai bagian dari strategi penelitian kualitatif, fenomenologi memiliki karakteristik sebagaimana penelitian kualitatif lainnya yang menekankan pada keterlibatan mendalam antara peneliti dan yang diteliti. Strategi ini sesuai untuk penelitian yang bersifat eksploratif, dengan menekankan pada objek sebagai suatu keutuhan kualitatif yang perlu dipahami secara menyeluruh. Terlebih dalam 99 pendekatan fenomenologi yang menekankan pada peleburan jarak antara pengamat dan yang diamati sehingga peneliti memiliki kesadaran dan pemahaman sebagaimana pihak yang diteliti. Dalam upaya mereduksi jarak ini, bias yang dimiliki peneliti perlu untuk diakui. Cirebon yang ada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki karakter budaya yang khas. Peneliti yang sejak lahir tinggal di Yogyakarta memiliki latar belakang kultur Jawa yang kuat. Perbincangan peneliti dengan generasi tua terjalin dengan mudah dengan Bahasa Jawa halus yang biasanya mereka juga fasih. Dengan generasi yang lebih muda perbincangan lebih mudah dilakukan dengan Bahasa Indonesia mengingat mereka lebih terekspos dengan budaya dan bahasa Sunda populer di Indramayu dan sekitarnya. Untuk itu, perlu senantiasa dilakukan klarifikasi agar makna dapat dikonfirmasi. Groat dan Wang (2013) lebih lanjut memaparkan sejumlah karakteristik penting penelitian kualitatif ini yang antara lain dipahami sebagi berikut. Pertama, diperlukan pendalaman seting alami secara komprehensif, dalam hal ini keterkaitan antara objek (warga dan arsitektur) dengan lingkungan sekitarnya harus senantiasa terjaga dalam hubungan yang sealami mungkin. Kedua, penelitian hendaknya berfokus pada penafsiran makna, peneliti diharapkan menjalin keterlibatan yang mendalam sehingga mampu memahami tindakan dan simbol-simbol kultural yang terbentuk dan menafsirkannya menjadi suatu sistem makna. Ketiga, penelitian berfokus pada cara responden memahami situasi, dengan berupaya sejauh mungkin memahami kesadaran masyarakat setempat. Berikutnya, agar dapat membangun pemahaman secara multi-dimensional diperlukan penggunaan taktik beragam baik dalam menghimpun maupun mengolah informasi. Penekanan pada logika induktif penting untuk dikembangkan mengingat dalam cara pandang holistik dan kompleks ini logika kausalitas dan sekuensial kurang relevan. Dalam menjalankan kajian ini peneliti berupaya untuk melakukan pendalaman secara komprehensif. Observasi terhadap bangunan secara fisik yang dilengkapi dengan perekaman fotografis, sketsa, pengukuran dan pencatatan 100 dilakukan untuk mendapatkan gambaran entitas fisik objek yang dikaji. Observasi terhadap aktivitas dilakuan dengan mengamati prosesi Memayu pada tahun 2014 dan 2015, serta Buka Sirap pada tahun 2015. Kunjungan terakhir ke Trusmi dilakukan pada bulan Mei 2016 pada saat tidak berlangsung upacara. Peneliti juga melakukan wawancara terbuka dengan berbagai kalangan, khususnya para pengelola Kramat. Perbincangan dengan Sep, kunci, kiai dan kemit serta para pemilik Bale Gede dilakukan untuk memahami peristiwa, makna, riwayat dan keterlibatan mereka dengan Kramat dan bangunan-bangunan terkait. Secara khusus dilakukan wawancara mendalam dengan Kiai Warlan, Sep Tony dan Abdul Khamid, seorang tukang muda. Kiai Warlan adalah mantan kiai di Kramat yang mengundurkan diri pada tahun 2010. Pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah, tradisi dan situasi di Kramat dari masa ke masa adalah informasi yang berharga. Terlebih Kiai Warlan juga memiliki kemampuan bertukang sehingga sangat memahami teknik membangun sekaligus memiliki kapasitas spiritual untuk menjalani ritual. Sep Tony adalah pemimpin baru di Kramat yang mulai berdinas pada tahun 2012. Dia memiliki kecenderungan untuk melakukan penafsiran simbolik kultural ketimbang pemaknaan yang bersifat praktikal. Abdul Khamid memiliki pengalaman terlibat lebih dari sepuluh kali Memayu dan beberapa kali Buka Sirap. Sehari-hari dia bekerja sebagai tukang meubel sehingga memiliki kecakapan teknis yang tinggi. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan di Trusmi, penulis tinggal di rumah Kiai Warlan bersama-sama dengan puluhan peziarah lainnya yang memadatinya. Di dalam rumah ini terdapat Bale Gede yang paling lengkap yang juga diziarahi oleh berbagai kalangan. Memayu untuk Omah Gede ini biasa dilakukan sepekan setelah Memayu di Kramat, Pertama kali datang menjelang Buka Sirap di tahun 2014, peneliti dan tim diterima sebagai peziarah sehingga dipersilakan untuk berdhikir dan berdoa di Bangsal di depan Makam Ki Buyut bersama peziarah lain yang datang bersamaan. Pada hari berikutnya peneliti sudah terlibat dalam Buka Sirap sebagai pengobeng yang turut mengerjakan hal-hal yang sangat sederhana dan menikmati makanan di 101 sana. Partisipasi sederhana dalam dua prosesi itu memungkinkan penulis untuk mendapat gambaran yang lebih dekat tentang pelaksanaan upacara pembaruan bangunan dan nilai penting yang disandangnya. Gambar 3.1. Wawancara dengan Sep Tony Informasi dari berbagai wawancara dicatat dalam buku catatan lapangan untuk kemudian direkonstruksi ke dalam narasi. Informasi yang berupa foto dan pengukuran dituangkan dalam bentuk gambar untuk disusun menjadi peta-peta tematis tentang material, pembanganan, aktivitas dan sebagainya. 3.6 Kerangka Kajian Keseluruhan Kajian ini disusun dalam kerangka sebagaimana berikut. Setelah landasan kajian yang berupa perumusan isue, masalah dan metoda disusun maka dilakukan pengamatan fenomenologis di Kramat Buyut Trusmi. Hasil amatan ini disajikan dalam thick description atau paparan mendalam guna mendapatkan gambaran tentang arsitektur dengan ketidak-panggahan dan konteksnya secara komprehensif. Kerangka paparan ini dikembangkan tiga tema dasar yakni 102 a) Konteks Kramat Buyut Trusmi yang terdiri atas konteks spasial (lokasi dan relasi), temporal (ingatan kolektif dan riwayat) dan sosial (para pelaku dan masyarakat) b) Objek yang terdiri atas ruang, bangunan dan tektonika c) Tindakan membangun yang melibatkan ketidak-panggahan yakni Memayu, Buka Sirap dan Pemugaran Hasil observasi fenomenologis yang berupa paparan mendalam ini dianalisis dengan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan konsep-konsep yang mendasarinya. Arsitektur yang melibatkan ketak-panggahan di Trusmi dipahami sebagai suatu proses pengelolaan material menjadi suatu konstruksi dalam suatu pemahaman terhadap tempat dan waktu yang khas. Untuk itu, konsep dasar yang dirumuskan diawali dengan pemahaman tentang tempat dan waktu guna memahami landasan pemikiran yang esensial, yang kemudian diikuti dengan konsep tentang sifat-sifat material dan relasinya dengan arsitektur. Setelah material ditransformasikan menjadi komponen bangunan dimulailah proses konstruksi yang konsep dasarnya dikaji pada bagian terakhir dari penafsiran ini. Konsep-konsep tersebut diabstraksikan sehingga menjadi rumusan pengembangan teori yang divalidasi dengan beberapa teori terkait. Secara keseluruhan, kajian disimpulkan sebagai pemaknaan terhadap suatu tradisi yang senantiasa menghidupkan momen asalinya sehingga komponen-komponen sistem arsitektur dalam teori Norberg-Schulz (2000) dan Klassen (1990) dapat selalu berhubungan dan terkait baik dalam tataran aktivitas mental maupun aktivitas fisik. 103 104 3.7 Kerangka Penulisan Proses dan hasil kajian di atas maka disusun dalam kerangka sebagimana berikut: Bab 1 Pendahuluan, berisi isu-isu yang terkait dengan fokus penelitian ini yakni teori-teori arsitektur yang didasari pada pemahaman tentang arsitektur sebagai objek yang panggah dan praktik berarsitektur di Nusantara yang memiliki karakter ketidak-panggahan yang kuat. Kesenjangan ini menjadi landasan pemilihan objek untuk dikaji, pemilihan teori untuk dikembangkan, serta perumusan masalah penelitian. Bab 2 Kajian Pustaka, berisi ulasan tentang teori sistem arsitektur dan relasinya dengan kepanggahan untuk memetakan kedudukan kajian ini. Bagian ini diikuti dengan perumusan landasan teori yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian. Bab 3 Metoda Penelitian, berisi perumusan strategi dan pendekatan untuk menyusun metoda penelitian yang didasarkan pada karakteristik hal yang dikaji dan karakteristik teori yang akan dikembangkan. Berdasar kedua karakteristik tersebut direncanakanlah penelitian dengan strategi kualitatif dan pendekatan fenomenologi hermeneutika. Bab 4 berisi paparan fenomenologis tentang Kramat Buyut Trusmi dan praktik berarsitektur di tempat itu sebagai fenomena yang dikaji untuk mengembangkan teori arsitektur. Kramat Buyut Trusmi dipandang sebagai fenomena khas dari masa awal pembentukan permukiman di tempat ini sehingga menyandang nilai-nilai dasar yang penting dan terlestarikan dalam bentuk fenomena fisik dan sosial tersebut. Bab 5 berisi pemaknaan hermeneutika yang diungkapkan ke dalam perumusan konsep-konsep dasar yang diturunkan dari kajian mendalam terhadap fenomena yang terdiri atas konsep tentang tempat, waktu, meterial dan konstruksi. Tempat dan waktu adalah pemaknaan atas eksistensi asasi Kramat Trusmi; sedangkan 105 material dan konstruksi adalah perwujudan bendawi yang melandasi ketidakpanggahan. Bagian ini difokuskan pada upaya membangun konsistensi dan koherensi internal dari unit-unit fenomena yang ada untuk membangun landasan konseptual Kramat Buyut Trusmi secara komprehensif. Bab 6 berisi abstraksi teoretik dari konsep yang sudah disusun pada bab sebelumnya guna mengembangkan teori Norberg-Schulz tentang the Presence of Architecture dan Klassen tentang the Process of Architecture dengan muatan aspek ketak-panggahan sebagaiman dijumpai di Kramat Buyut Trusmi. Bab 7 berisi penyimpulan dari keseluruhan kajian secara ringkas dan sistematis guna menegaskan bahwa pertanyaan penelitian telah dijawab dengan baik, serta perumusan saran-saran untuk kajian berikutnya. 106 BAB 4 MEMBANGUN ARSITEKTUR, TEMPAT DAN RELASI DI KRAMAT BUYUT TRUSMI 4.1. Pengantar Arsitektur di lingkungan Kramat Buyut Trusmi menjalin hubungan yang sangat intim dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan yang berafiliasi dengannya. Meskipun tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan keseharian, Kramat ini tidak pernah sepi dari pengunjung yang datang dari desa itu atau dari tempat yang lebih jauh. Peziarah datang setiap hari terlebih di malam Jumat. Pada saat hari perayaan jumlah itu menjadi puluhan kali lipat. Bangunan-bangunan di lingkungan Kramat ini senantiasa diperbarui dalam prosesi Memayu yang dilaksanakan setiap tahun dan Buka Sirap yang dilaksanakan setiap empat tahun. Ribuan orang terlibat dalam berbagai perannya di hari-hari prosesi tersebut. Berbeda dari kebanyakan arsitektur yang dibuat oleh kalangan yang terbatas dan dipergunakan oleh kalangan yang lebih luas, arsitektur di Kramat Buyut Trusmi boleh dikata dibuat dan dipergunakan oleh seluruh warga. Dengan menanak nasi, memotong kayu, dan menimba air atau sekedar memindahkan welit yang telah usang dan memotong sayur, seseorang telah berkontribusi dalam membuat arsitektur. Secara konseptual dia bukan hanya “user” tetapi juga “maker”. Untuk memahami arsitektur yang kompleks ini diperlukan observasi yang serba cakup guna membangun paparan naratif yang mendalam. Dengan paparan tersebut arti penting arsitektur dan upaya untuk membinanya dapat dipahami dengan lebih substansial. Suatu paparan mendalam memungkinkan pengamat untuk mengenali intensi di balik tindakan atau fenomen yang kelihatannya serupa. Memperbaiki bangunan karena memenuhi kebutuhan teknis semata dan memperbarui bangunan dengan tujuan simbolis mungkin melibatkan material dan kecakapan yang 107 sama. Suatu paparan mendalam dengan mengaitkan antara fenomena dan konteksnya memungkinkan pengkaji untuk membedakan keduanya. Paparan ini adalah hasil observasi dalam momen yang berkaitan dengan Buka Sirap dan Memayu di tahun 2014 dan 2015. Bab ini diawali dengan penyajian tentang latar sejarah, kultural dan geografis untuk memberikan konteks keberadaan Kramat Buyut Trusmi. Berikutnya, adalah paparan tentang lingkungan binaan Kramat tersebut beserta pelaku dan aktivitas mereka. Bagian-bagian ini membentuk setting pemaparan berikutnya. Bagian utama yang disajikan terakhir adalah paparan yang lebih rinci tentang tektonika bangunan-bangunan di Kramat Buyut Trusmi. Bagian ini diikuti dengan penyajian tentang prosesi Buka Sirap dan Memayu sebagai perwujudan pembangunan kembali secara berkala yang merupakan inti dari kajian ini. Pengembangan bangunan secara non-periodik memberikan gambaran tentang proses diakronik yang terjadi di Kramat Buyut Trusmi. 4.2. Ingatan Kolektif yang Terpenggal Sebagai kawasan pesisir di perairan dengan jalur niaga yang ramai, Cirebon menjalin interaksi yang intensif dengan berbagai peradaban yang melintasi Laut Jawa dan Selat Malaka. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Nusantara kawasan pesisir utara ini mengalami berbagai perubahan karena interkasi tersebut. Perubahan secara meluas dan mendasar dalam kehidupan di Nusantara terjadi dengan pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya sejak paruh terakhir abad ke-15. Sejarawan Ricklefs (2001) berargumen bahwa kehadiran Islam adalah momentum yang mendasari perkembangan era modern di Indonesia. Periode awal pembentukan kekuasaan Islam di Jawa ini sangat penting, namun juga sangat kabur lantaran kelangkaan sumber-sumber tertulis dari masa tersebut. Di antara kisah-kisah itu adalah tokoh pewarta Islam yang pertama di belahan barat pulau Jawa ini adalah putra dari Raja Hindu Pajajaran yang bergelar 108 Siliwangi dengan seorang wanita Muslimah keturunan Champa yang berada di Vietnam sekarang. Dalam bayang-bayang narasi samar inilah tokoh pendiri kota bandar Cirebon dan Trusmi muncul. Kisah tentang tokoh yang diyakini sangat penting dalam meletakkan landasan pengembangan masyararakat Muslim dan pembentukan kuasa mandiri di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini dipaparkan dengan berbagai ragam alur dan tumpang tindih antara satu tokoh dan tokoh lainnya. Dalam banyak versi tokoh ini disebut sebagai Pangeran Walangsungsang. Sang Pangeran adalah putra Prabu Siliwangi sekaligus pemuka pertama yang memeluk Islam. Di Trusmi, Walangsungsang dikisahkan mendirikan kota Cirebon—sehingga bergelar Mbah Kuwu Cirebon—kemudian menyerahkan kota tersebut kepada adiknya yang dikenal sebagai Sunan Gunungjati untuk bertahta di sana dan menurunkan dinasti para Sultan Cirebon. Naskah yang disusun oleh Ki Ahmad, Sep Kramat Trusmi yang meninggal pada tahun 2012, mengajukan pemahaman bahwa Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabuwana, Mbah Kuwu Cirebon dan Ki Buyut Trusmi adalah orang yang sama yang mendirikan kota Cirebon sekaligus Kabuyutan Trusmi; dan tokoh cikal bakal ini dimakamkan di Kramat Buyut Trusmi. Dengan penggabungan ketiga tokoh dalam satu figur dan meyakini keberadaan jasadnya di Kramat ini, orang Trusmi memiliki klaim atas senioritas leluhur mereka terhadap semua masyarakat Muslim pasca Pajajaran. Akan tetapi dikisahkan kemudian bahwa Ki Buyut Trusmi yang menikahi putri Ki Gede Alangalang tidak memiliki keturunan. Murid-muridnyalah yang melanjutkan upaya penyebarluasan Islam dan pembentukan masyarakat Muslim. Murid yang paling utama disebut sebagai Ki Gede Trusmi yang lalu mendirikan Omah Gede yang menjadi kediamannya, beberapa puluh meter di sebelah barat kompleks Kramat Buyut Trusmi. Hubungan Trusmi dengan Kraton Cirebon terjalin dengan kompleks antara klaim senioritas Trusmi dan hegemoni Kraton Cirebon. Di satu sisi, orang-orang 109 Trusmi meyakini supremasi dan senioritas Desa mereka dan cikal bakalnya ketimbang Kraton Cirebon. Kramat Trusmi terletak di bagian yang lebih hulu ketimbang Kramat Gunungjati. Di sisi lain, Trusmi hanyalah desa kecil yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Cirebon. 4.3. Membangun Tempat, Menjalin Relasi Orang-orang Trusmi meyakini bahwa desa mereka sebelumnya adalah hamparan tanah yang ditumbuhi alang-alang dengan pemukim pertama yang disebut sebagai Ki Gede Alang-alang. Setelah Ki Gede menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Walangsungsang maka tempat ini kemudian dikembangkan sebagai permukiman yang ramai. Di tengah desa ini terdapat Sungai Glagah yang mengalir ke utara menuju Laut Jawa. Saat ini debit air sungai ini sangat kecil karena sedimentasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemungkinan di masa silam Sungai Glagah memegang peran transportasi yang penting. Salah satu benda yang dipusakakan di Desa Trusmi adalah minatur perahu dengan panjang sekitar 1,2 meter yang saat ini disimpan di Bale Gede Bangbangan. Beberapa orang mengenang benda ini sebagai kendaraan Ki Buyut Trusmi kalau bepergian yang mestinya melalui sungai tersebut. Dengan berkedudukan tepat di samping sungai, relasi hulu dan hilir menjadi sangat terasa di sini. Lokasi Trusmi menjadi penanda sejarah tentang hubungan antara Kerajaan Pra-Islam Pajajaran yang terletak di pedalaman dengan Kerajaan Islam Cirebon yang terletak di pesisir. Ki Buyut Trusmi yang diyakini sebagai seorang pangeran Pajajaran dan pendiri kota Cirebon mendapatkan kedudukan geografis di bentang alam yang khas tersebut. Terdapat dua gerbang menghadap ke selatan mengapit kompleks Kramat Buyut Trusmi. Gerbang timur mengantarkan kita ke ruang terbuka yang cukup luas yang biasa disebut sebagai alun-alun. Gerbang barat berupa gerbang bentar atau split gate yang berbentuk seperti candi yang terbelah. Terbuat dari pasangan bata yang bercat merah, gerbang ini tampak jauh lebih kuna dari pada gerbang timur. 110 Gambar 4.1. Kompleks Kramat Buyut Trusmi 111 Dalam kaitannya dengan peziarahan dan upacara saat ini, gerbang barat ini memiliki peran yang lebih penting ketimbang gerbang timur. Para peziarah sebagian besar masuk ke kompleks Kramat melalui gerbang ini lantaran tempat untuk melapor kepada pengelola Kramat berada di dekat gerbang ini. Saat penyelenggaraan prosesi menjelang Memayu, misalnya, gerbang barat juga memainkan peran penting mengingat semua peserta prosesi yang bersifat ritual diberangkatan dan kembali ke Kramat melalui gerbang ini. Berbagai kalangan yang diwawancarai di Trusmi semua menyebutkan bahwa semasa hidupnya, tokoh cikal bakal ini berkediaman di kompleks yang kemudian menjadi makamnya setelah wafatnya. Alun-alun ini berupa ruang terbuka dengan pepohonan besar di tepiannya dan lapangan volley di sisi barat. Sebuah sungai kecil yang memisahkan lapangan dengan kompleks makam Trusmi. Dengan melintasi jembatan kecil kita dapat mencapai gapura Kramat Buyut Trusmi yang menghadap ke timur. Dari pintu gerbang bentar barat kita melintasi jalan setapak sekitar seratus meter sehingga mencapai gerbang bentar kedua yang terletak tepat di sudut barat daya komplek Kramat. Undak-undakan pada sisi bawah gapura ini menjadi penghalang bagi kendaraan untuk melintasinya. Gerbang yang serupa terletak di sudut barat laut kompleks. Di antara kedua gerbang ini terletak gapura Kramat yang menghadap ke barat. Kedua gapura itu beratap limasan bersusun dua dengan bubungan pendek yang ditopang oleh delapan tiang. Sepasang daun pintu berukir terpasang di bawah ambang gapura ini. Batur dengan beberapa undak-undakan yang terbuat dari pasangan bata membentuk bagian bawah gapura ini. Belakangan ini permukaan undak-undakan tersebut dilapis dengan ubin mosaik dengan pertimbangan praktis agar tidak licin diinjak dan mudah dibersihkan. 112 Gambar 4.2. Kelompok bangunan di sekitar Gapura Timur (A): Balong Pakulahan (B), Witana (C), Masjid (D), Pawadonan (E) dan Gerbang pertama menuju Makam (F) Gambar 4.3. Kelompok bangunan di sekitar Kabuyutan (A): Gerbang pertama (B), Jinem Wetan (C), Jinem Kulon (D), Pendopo (E), Bale Pasalinan (F), Batu Pendadaran (G), Gerbang kedua (H), dan Bangsal Peziarahan (I) 113 Gambar 4.4. Kelompok bangunan di sekitar Gapura barat (A): Paseban (B), Bale Kiai (C), Bale Kunci (D), Bale Keprinci (E), Jinem Wadon (F), Sumur Kejayan (G) dan Masjid (H) Di balik kedua gapura ini terentang dinding masif setinggi dua meter yang menghalangi pandangan menerus ke dalam kompleks Kramat. Dinding penyekat ini biasa disebut di Trusmi sebagai kuta hijab. Kuta berasal dari bahasa Jawa yang berarti kota atau lingkungan perkotaan yang dibatasi oleh benteng sedangkan hijab dari bahasa Arab yang berarti penyekat atau penutup pandangan yang sering dipergunakan untuk menyebut kain pembatas ruang atau penutup aurat. Kuta hijab ini memang berperan menghalangi pergerakan lurus adan pandangan yang menerus dari luar ke dalam kompleks. Kesemua komponen tersebut menegaskan pemisahan antara ruang dalam kompleks Kramat Buyut Trusmi dengan ruang luar di sekitarnya. Semua orang yang memasuki kedua gerbang ini dipersilakan untuk melepaskan alas kaki sebagaimana tulisan yang tertera pada kuta hijab tersebut. Hal ini mengungkapkan pemahaman bahwa lingkungan di Kramat Buyut Trusmi bersifat suci, berbeda dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Di balik gapura timur terdapat kolam penyucian yang disebut sebagai Balong Pakulahan, sedangkan di balik 114 gapura barat terdapat Sumur Keramat. Kedua elemen air—kolam dan sumur—ini menegaskan lebih lanjut tentang prinsip area suci di dalam kompleks. Di dalam kompleks tersebut terdapat tak kurang dari sepuluh bangunan dengan berbagai ukuran. Namun demikian, dengan pagar keliling yang masif kita hanya bisa melihat atap bangunan tersebut yang tampak menonjol di balik pagar. Dengan segera dari luar kompleks dapat ditengarai bahwa sebagian bangunan tersebut beratap alang-alang, sedangkan yang lain beratap sirap kayu. Kontras antara tembok pagar yang dicat merah secara berkala dengan atap-atap yang bewarna kuning keabu-abuan menjadi ciri utama kompleks ini dilihat dari area di sekitarnya di sekitarnya. Gapura barat dan timur Kramat Buyut Trusmi dihubungkan oleh serangkaian ruang terbuka dengan bentuk tak beraturan dengan susunan memanjang sehingga membentuk seperti jalur jalan setapak di sela-sela bangunan. Makam dan bangunan untuk para penjaga makam terletak di sisi utara jalur ini sedangkan masjid dan beberapa bangunan lainnya terletak di sisi selatan jalur tersebut. Dengan jalur yang membagi dua kompleks ini, makam dan masjid menjadi pusat berganda. Konfigurasi ganda dengan jalur menerus ini sangat berbeda dengan makam keramat di Jawa pada umumnya termasuk makam Sunan Gunungjati yang terletak dekat Kramat Buyut Trusmi. Makam-makam tersebut memiliki jalur sirkulasi yang klimatis, yakni, berawal di gapura depan dengan jalur pejalan kaki yang berupa jalan setapak atau undak-undakan mendaki di belakangnya. Masjid berada di dekat pintu masuk atau di salah satu sisi jalur tersebut. Setelah melalui sejumlah halaman dan gapura akhirnya seseorang mencapai akhir jalur letak makam junjungan yang dimuliakan sebagai klimaks bagi perjalanan peziarahan. Dari gapura barat kita mencapai Paseban, yang berupa bangsal besar tak berdinding. Di tempat ini para pengelola Makam menerima tetamu yang akan berziarah di kompleks Kramat Buyut Trusmi. Keberadaan Paseban ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan peziarahan gapura baratlah yang diutamakan. 115 Bangsal Paseban ini menjadi titik perjumpaan dan pertukaran. Seseorang yang akan berziarah atau tirakat akan menghadap pengelola Kramat di sini untuk mohon ijin melakukan kegiatan spiritualnya. Seorang Kemit atau staf yang melayani peziarah akan mendampinginya berikutnya. Saat upacara, seperti Muludan, Memayu dan Buka Sirap, para donatur datang ke tempat ini menyampaikan sumbangan mereka. Sebagai gantinya, di tempat ini mereka akan mendapat makanan atau benda lain yang dianggap memiliki berkah seperti abu bekas kemenyan, kapur tohor bekas makan sirih atau air dari sumur keramat. Bangunan di sekitar Paseban menunjang perjumpaan tersebut. Di sisi timur Paseban terdapat Bale Kiai dan Bale Kunci tempat para pengelola Kramat berdinas sekaligus tempat untuk menyimpan bahan makanan dan makanan sumbangan. Di sisi utara terdapat dapur untuk mengolah hasil sumbangan yang berikutnya makanan tersebut akan didistribusikan kembali kepada warga dan peziarah. Di sisi selatan terdapat pendopo kecil untuk mementaskan sumbangan yang berupa kesenian yang ritualistik yang disaksikan dari Paseban. Gambar 4.5. Kenduri di Paseban usai Buka Sirap 116 Di selatan Paseban terdapat Masjid Kramat Buyut Trusmi. Bangunan utama Masjid ini berdenah persegi dengan atap piramidal bersusun tiga sebagaimana lazimnya masjid-masjid di Jawa. Serambi yang dinaungi dua atap limasan terletak di sisi timur dengan ruang yang tertutup dinding. Di utara Masjid terdapat Sumber air yang disebut Sumur Kejayaan yang diyakini memiliki nilai keberkahan tertentu. Sumur air ini dianggap berpasangan dengan Balong Pekulahan di timur sehingga banyak pengunjung yang mandi di kedua tempat tersebut. Ruangan-ruangan untuk wanita tedapat di sisi selatan dan barat Masjid. Ruang beratap alang-alang yang menempel di sisi selatan masjid dipergunakan bagi permpuan untuk melaksanakn ibadah shalat. Sementara, bangunan terpisah berdinding rapat di barat Masjid berfungsi sebagai tempat untuk perempuan bertirakat sehingga disebut Jinem Wadon. Berjalan lebih lanjut ke arah timur kita akan menjumpai gapura menghadap ke selatan dengan pohon Kapianjing (Cynometra cauliflora) di depannya. Nama pohon ini diasosiasikan dengan seruan untuk “manjing” atau masuk ke dalam makam melalui gapura ini. Di kiri kanan gapura terdapat wadah air besar yang terbuat dari tanah liat yang dapat dipahami sebagai isyarat untuk menyucikan diri sebelum memasuki tempat di belakangnya. Di belakang gapura ini terdapat halaman depan makam yang dikelilingi oleh sejumlah banguna. Di kiri dan kanan halaman terdapat sepasang bangunan yakni Jinem Wetan dan Jinem Kulon. Kedua bangunan ini berfungsi utama untuk tirakat. Di sisi utara halaman terdapat gapura dalam menuju makam dengan pendopo di depannya. Tepat di barat gapura ini terdapat bangunan kecil yang tertutup yakni Bale Pasalinan tempat para pengelola Kramat berganti busana putih sebelum melaksanakan tugas. Secara keseluruhan dari gapura barat seseorang dapat menghayati tahapan tahapan penyucian sebelum mencapai makam. Di samping Pasalinan terdapat 17 batu bulat dengan berbagai ukuran yang disusun melingkar berurutan dari yang paling kecil hingga yang terbesar yang berada 117 di tengah. Beberapa peziarah berjalan berkeliling dan mengangkat batu-batu tersebut satu persatu. Masyarakat setempat menyebutnya Batu Pendadaran. Gapura di sisi utara halaman depan tersebut menuju ke halaman dalam makam. Di tengah halaman ini terdapat bangunan utama tempat Ki Buyut Trusmi dan para pengikut pertamanya dimakamkan. Bangunan berdenah persegi panjang ini tertutup rapat dengan pintu yang sangat rendah. Hanya Sep, keempat Kiai dan keempat Kunci yang boleh memasukinya. Di antara Kabuyutan dan gapura terdapat pendopo besar yang menaungi peziarah yang sedang berdoa di depan pintu makam. Pendopo dalam yang kadang disebut Pasujudan ini dibangun pada dasawarsa 1950-an sehingga hampir berbarengan dengan gapura depan makam yang berukir angka tahun 1958. Kompleks Kramat Buyut Trusmi ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat peziarahan tetapi juga menjadi tempat cikal bakal pertumbuhan kawasan (Adimuryanto, 2001). Masyarakat meyakini bahwa dari Kramat tumbuh permukiman Blok Jero sebagai area hunian pertama di lingkungan ini. Dari Blok Jero berkembang menjadi empat Blok lain yakni: Blok Bangbangan, Blok Sibunder, Blok Klentikan dan Blok Kebonasem. Pola ini sangat mirip dengan pola mancapat pada masyarakat Jawa kuna dengan pusat yang dikelilingi oleh empat pusat sekunder. Gambar 4.6. Pola pengembangan permukiman Trusmi 118 4.4. Pelaku, Hubungan Sosial dan Aktivitas Mereka Pelaku dari berbagai kalangan beraktivitas dan mengambil bagian dalam berbagai peristiwa yang terselenggara di Kramat Buyut Trusmi. Mereka hadir dan memosisikan diri di dalam ruang, berinteraksi dan menjalin hubungan sosial, serta membangun makna dan pemahaman di Kramat. Para pelaku di lingkungan ini memiliki intensitas dan kedekatan yang beragam yang secara lebih rinci dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) Para pengelola Kramat Buyut Trusmi. Mereka sehari-hari berkedudukan di tempat ini, memiliki kewenangan penuh terhadap lingkungan fisik serta menyelenggarakan kegiatan di Kramat baik yang bersifat ritualistik maupun keseharian. b) Warga Trusmi. Mereka berperan sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan ritual, keseharian dan pembangunan di Kramat. Warga tersebut mengkontribusikan dana, material, tenaga dan pemikiran mereka untuk terselenggaranya berbagai aktivitas maupun terlestarikannya lingkungan fisik Kramat. Pada saat salah satu dari para pengelola Kramat meninggal atau mengundurkan diri warga tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih yang akan mengubah statusnya dari warga menjadi pengelola. c) Peziarah dan pelaku tirakat adalah orang luar yang mengambil bagian dalam aktivitas di Kramat Buyut Trusmi dalam waktu yang singkat. Mereke sepenuhnya terikat pada aturan dan tak memiliki kewenangan untuk mengatur. Dengan memberikan kontribusi yang besar, seorang peziarah dapat berubah menjadi warga yang turut mengembangkan kegiatan dan lingkungan di Kramat meskipun tetap dalam posisi sub ordinat. Dalam kaitannya dengan pembentukan dan penggunaan ruang, masingmasing pelaku tersebut memiliki peran yang berbeda. Para pengelola memiliki 119 kewenangan untuk mengatur aktivitas dan mengarahkan pembentukan ruang. Para pengunjung menjadi pendukung langsung kebijakan pengelola dan memberi masukan terhadap aktivitas dan ruang namun tak memiliki kewenangan kendali langsung. Para peziarah mendapatkan kemanfaatan fungsional dan spiritual dari pengelolaan tapi hanya beraktivitas dan berperan dalam waktu yang singkat. 4.4.1. Pengelola Kramat Pengelolaan Kramat Buyut Trusmi dipimpin oleh seorang Sep. Secara teoretik siapapun warga Trusmi bisa menjadi Sep karena pemangku jabatan ini dipilih dari dan oleh kalangan laki-laki dewasa yang turun temurun berkediaman di desa ini. Dalam memimpin Kramat, Sep dibantu oleh empat Kiai dan empat Kunci yang juga dipilih oleh masyarakat setempat. Selain itu terdapat empat Kaum yang mengelola Masjid. Kaum dipimpin oleh seorang Lebe yang dibantu oleh Ketib, Modin dan Merbot sebagaimana dijumpai di banyak masjid tradisional. Ketib bertugas menyampaikan khutbah, modin memimpin doa sedangkan merbot mempersiapkan sarana dan prasarana. Mengingat banyaknya kegiatan peziarahan yang perlu dilayani, masingmasing Kunci dibantu oleh sekelompok Kemit yang terdiri atas dua belas orang sehingga secara keseluruhan terdapat empat puluh delapan orang Kemit. Para Kemit ini bertugas secara bergiliran untuk melayani peziarah. Setiap empat hari sekali satu kelompok kemit menunaikan tugasnya. Dengan demikian secara total terdapat enam puluh satu orang yang mengelola Kramat. Akan tetapi orang Trusmi lebih suka menghitungnya dengan menganggap setiap kelompok Kemit sebagai satu orang sehingga didapat jumlah pengelola Kramat sebanyak tujuh belas orang. Bilangan 17 ini berkesesuaian dengan jumlah raka’at shalat dalam sehari semalam. Dalam kaitannya dengan pembangunan fisik kesembilan orang—Sep beserta para Kiai dan Kunci—memiliki kewenangan khusus atas bangunan Makam atau Kabuyutan. Hanya mereka yang boleh memasuki bangunan yang dikeramatkan tersebut, mebersihkan, memperbaiki dan mengubahnya. Ketika seorang donatur 120 menyumbangkan keramik untuk lantai Kabuyutan maka keramik tersebut harus dipasang oleh sembilan sesepuh Kramat ini. Begitu pula saat pelaksanaan prosesi penggantian sirap setiap empat tahun sekali. Sembilan orang ini, karenanya, perlu untuk memiliki kapasitas spiritual yang tinggi tapi juga kecakapan ketukangan yang memadai. Saat ini, tidak banyak orang yang dapat memenuhi idealita tersebut sehingga terjadi kesenjangan teknis dalam beberapa hal. Di antara kesenjangan yang beberapa kali terjadi adalah dalam penyiapan bahan dan alat, serta pengelolaan para tukang. 4.4.2. Warga Desa Trusmi Warga Trusmi memiliki hubungan yang khusus dengan Kramat Buyut Trusmi. Ki Buyut wafat tanpa meninggalkan keturunan sehingga tidak ada kelompok elit yang merupakan trah yang dapat mengklaim memiliki hak-hak khusus atas Kramat. Semua warga dengan demikian memiliki hubungan yang sama dekatnya dengan Kramat dan cikal bakal Desa ini. Hal ini adalah salah satu faktor penting untuk memahami tingginya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Kramat. Desa Trusmi terbagi menjadi lima blok yang didasarkan pada asal-usul kesejarahan. Blok ini juga berperan sebagai satuan untuk mengelompokkan warga saat upacara seperti Buka Sirap. Blok tersebut meliputi: Blok Jero sebagai inti yang dikelilingi oleh Blok Bangbangan, Blok Sibunder, Blok Klentikan dan Blok Kebonasem. Bererapa desa tetangga yang warganya turut berpartisipasi mendapat status sebagai blok juga seperti Blok Gamel, Blok Talitengah, Blok Sibendo dan Blok Wotgali. Dalam kaitannya dengan pembangunan fisik, warga Desa Trusmi menjadi penyumbang utama. Koran setempat mengutip bahwa biaya yang dikeluarkan saat Buka Sirap tahun 2014 mencapai 2,4 milyar rupiah yang semua didapatkan dari kontribusi warga baik dalam bentuk tunai, tenaga maupun barang seperti kayu jati dan binatang ternak yang seringkali melebihi kebutuhan (Pikiran Rakyat, 8/9/2014). Para pengelola Kramat bangga bahwa semua ini bisa didapatkan tanpa harus meminta sumbangan kepada para donatur. 121 Warga selaku donatur meyakini bahwa dengan menyumbangkan barang, uang dan tenaga yang mereka miliki mereka akan mendapatkan berkah. Kadang transmisi berkah tersebut didapat warga dalam bentuk konkret seperti alang-alang dan sirap bekas atau minyak dan gabah yang telah dikemas oleh pengelola Kramat tapi kadang dalam bentuk abstrak seperti kesempatan untuk menyentuh sirap dan welit saat dilepaskan dari bangunan-bangunan di Kramat. Dalam pertukaran yang terjadi terus menerus inilah ikatan sosial-spiritual antara warga dengan Kramat dilestarikan. 4.4.3. Pelaku Ziarah Dan Tirakat Pelaku yang memiliki hubungan yang paling longgar adalah peziarah yang melakukan kunjungan dengan motivasi spiritual ke Kramat Buyut Trusmi. Secara umum peziarah dibangi menjadi dua kelompok yakni peziarah dalam waktu yang singkat atau disebut wong ziarah dan peziarah yang bermalam di situ hingga beberapa hari atau biasa disebut sebagai wong tirakat. Wong tirakat menginap dan melakukan latihan spiritual dalam jangka waktu tertentu di Kramat. Wong tirakat laki-laki berkediaman di Jinem Kulon dan Jinem Wetan yang terletak di depan Makam Ki Buyut Trusmi sedangkan wong tirakat perempuan di Jinem Wadon yang ada di barat Masjid. Jika setelah ziarah dan tirakat seseorang mendapat apa yang dia cita-citakan maka seringkali orang tersebut menyumbang dalam jumlah yang besar kadang dalam bentuk komponen bangunan. Beberapa pembangunan di Kramat Buyut Trusmi terjadi atas inisiatif dan dukungan dana dari donatur. Penambahan AC di Masjid yang baru saja dilakukan atau penggantian lantai Kabuyutan dengan keramik adalah contoh pengembangan pada bangunan-bangunan penting di Kramat yang terjadi atas prakarsa donatur. 4.5. Tektonika: Bentuk, Konstruksi dan Ornamentasi Bangunan Bangunan-bangunan di kompleks Kramat Buyut Trusmi semua memiliki atap dengan empat sisi miring kecuali bangunan yang menaungi sumur dan salah satu cungkup yang dianggap minor yang beratap pelana. Bangunan-bangunan tersebut 122 memiliki puncak yang bermacam-macam. Bangunan utama masjid berpuncak lancip serupa piramida yang di Jawa biasa disebut tajug. Bangunan Makam, Pendopo di depan Makam, Witana, serambi Masjid dan Bale Pasalinan memiliki bubungan yang relatif pendek. Tipe bangunan ini di Jawa lazim disebut sebagai joglo. Beberapa bangunan yang lain memiliki bubungan yang panjang yang di Jawa lazim disebut sebagai limasan. Bangunan ini adalah semua gapura, Paseban, Pendopo dan Jinem Lanang maupun Wadon. Namun demikian di Trusmi dan di Cirebon pada umumnya semua bentuk bangunan tersebut disebut sebagai limasan tanpa memiliki sub-varian yang membedakan secara lebih rinci antar bentuk bangunan yang ada di situ. Dalam pemaparan ini semua bangunan tersebut juga disebut sebagai limasan kecuali bangunan beratap lancip yang disebut sebagai atap tajug mengingat bentuk, konstruksi dan perlakuan terhadap bangunan ini di Trusmi cukup berbeda. 4.5.1. Gapura Bangunan-bangunan gapura yang dinaungi oleh atap yakni gapura timur dan gapura barat serta dua gapura menuju ke makam. Kesemua gapura ini memiliki atap limasan dengan dua susun atap dengan alas berukuran sekitar 3,0 x 1,5 meter. Bukaan masing-masing gapura ini ditutup dengan sepasang daun pintu yang dihias dengan ukiran yang rumit dengan berbagai ragam hias di sisi yang menghadap ke luar. Ambang atas pintu pintu ini juga diukir dengan pola yang repetitif. Di atas balok ambang bukaan pintu terdapat tiga susun balok yang ditumpuk dengan posisi melebar ke atas ke semua arah sehingga berbentuk seperti piramida berundak yang tersusun terbalik. Balok-balok yang tersusun menyerupai tumpang sari ini diukir di sisi yang menghadap ke luar dan ke bawah dengan ragam hias yang bahkan lebih rumit ketimbang balok ambang. Atap bagian bawah pada kedua gapura menuju makam tersebut ditopang oleh empat balok juga. Pertemuan sudut keempat balok penyangga teritis atap bagian bawah tersebut dihubungkan dengan teknik takikan (cathokan). Masing-masing balok panjang yang membujur timur-barat ditopang oleh sepasang konsol yang berupa balok miring yang bertumpu pada tiang. Balok-balok pendek dengan kedudukan 123 serupa yang membujur utara selatan ditumpu oleh pilar dinding pagar yang terbuat dari pasangan bata. Gambar 4.7. Gapura Timur Gapura timur memiliki konstruksi yang serupa dengan gapura makam namun balok-balok penyangga tepian atap bawah ditumpu oleh empat saka. Kedelapan saka tersebut berdiri di atas umpak yang berbentuk piramida terpancung. 4.5.2. Witana: Bangunan Asal-Muasal Struktur yang dianggap sebagai cikal bakal dari semua bangunan di kompleks Kramat Buyut Trusmi adalah Witana. Nama bangunan ini diyakini bersal dari kata “wiwitane ana” atau “ada sejak semula”. Bangsal tak berdinding berdenah persegi berukuran sekitar 3,5 x 3,5 meter ini memiliki atap bagian atas dengan bubungan yang sangat pendek yang membujur ke timur-barat. 124 Atap atas ini ditopang oleh empat saka guru berpenampang persegi berukuran sekitar 10 x 10 cm. Keempat saka ini dihubungkan dengan empat blandar pada sisi atas dan empat sunduk di bawahnya. Di atas masing-masing blandar ditumpang dua balok kecil. Balok yang ada di sisi luar ditakik untuk menempatkan usuk atap bagian atas maupun atap bagian bawah. Hanya balok blandar yang memiliki ujung menjorok (gimbal) sedangkan balok-balok di atasnya terhubung dengan pertemuan sudut. Ornamentasi bangunan ini relatif sederhana terbatas pada bangun-bangun geometris. Balok yang berada di sisi dalam diukir dengan profil berundak. Ujung atas saka guru tersebut dihias dengan ganja atau kepala kolom yang berbentuk bintang bersegi delapan yang terpancung dengan posisi melebar ke atas. Bagian pertemuan antara saka dan ganja ini membentuk “leher” yang sangat kecil. Ujung bawah saka ini berdiri di atas umpak batu. Sisi bawah balok blandar dan sunduk diukir dengan motif segitiga sangat lancip di kedua ujung tiap balok. Gambar 4.8. Bentuk bangunan dan struktur saka guru Witana 4.5.3. Kabuyutan Struktur terbesar di Kramat Buyut Trusmi adalah bangunan yang menaungi makam atau cungkup Ki Buyut Trusmi dan orang-orang terdekatnya yang biasa disebut Kabuyutan. Cungkup yang berupa bnagunan berdinding rapat ini berdenah persegi panjang dengan pintu kecil menghadap ke selatan dan bubungan yang membujur ke utara-selatan atau tegak lurus terhadap bubungan Bangsal Witana. 125 Bubungan cungkup, sebagai komponen yang terpasang paling tinggi pada bangunan yang paling dikeramatkan ini dibuat sangat khusus. Bubungan sepanjang 1,4 meter dan lebar 1,0 meter ini terbuat dari kayu jati gelondongan utuh yang dibentuk sedemikian rupa sehingga seperti terbuat dari dua papan yang dihubungkan siku-siku. Seorang tukang muda yang ikut dalam penggantian terakhir bubungan ini pada tahun 1998 mengisahkan bahwa bubungan lama yang diganti, menurut cerita yang didengarnya dari orang-orang tua setempat, berumur lebih dari 90 tahun. Di dalam cungkup ini disemayamkan Ki Buyut Trusmi dan kesembilan pengikut pertamanya. Nisan Ki Buyut Trusmi terletak di tengah ruang yang dikeliling empat saka guru sedangkan nisan para pengikutnya berjajar di sisi selatan atau di arah “kaki” makam utama. Sesuai dengan letak geografis dan ajaran Islam maka kesemua makam ini membujur dengan kepala di arah utara. Sisi utara ruang ini dibiarkan kosong. Teritis kecil ditambahkan di sisi barat bangunan ini. Teritis ini menaungi nisan yang saat ini bercat merah jambu yang dikatakan sebagai nisan istri Ki Buyut Trusmi yang berada di luar dinding makam tapi masih satu atap. Keempat saka guru cungkup ini memiliki ganja di ujung atasnya dan dihubungkan dengan blandar dan sunduk. Cungkup ini dilingkupi dengan dinding pasangan bata setinggi 1,5 meter dengan bukaan hanya pada pintu yang menghadap ke selatan. Pintu ini sangat rendah, dengan bukaan setinggi 1,2 meter, sehingga sangat menunjang kesan tertutup bangunan ini. Sebagai bangunan yang paling dikeramatkan, hanya Sep, keempat Kiai dan keempat Kunci yang boleh memasukinya. Informasi lebih rinci tentang ruang dalam bangunan ini didapat melalui wawancara. 126 Gambar 4.9. Bangunan Kabuyutan (kiri) dan Pendopo (kanan) Saat upacara penggantian sirap tahun 2014, dua lembar anyaman bambu (gedheg) berukuran sekitar 1 x 2 meter yang dibingkai dengan bambu belah dimasukkan ke dalam bangunan cungkup melalui sela-sela usuk di atap saat semua sirap diturunkan. Ki Warlan memaparkan bahwa gedheg tersebut dipergunakan untuk membuat naungan dalam yang melingkupi nisan Ki Buyut Trusmi. “Atap” gedheg di bawah atap sirap ini diganti dengan yang baru saat yang lama telah lapuk atau kadang ditambahkan menumpuk begitu saja. Penggantian atau penambahan atap gedheg itu dilakukan saat Buka Sirap mengingat hanya pada saat itu komponen yang cukup besar ini dapat dimasukkan. Atap susun kedua ditumpu oleh delapan saka yang terletak di sudut dan sisi atap dan berjarak sekitar 0,5 meter dari dinding keliling. Tepian bawah atap ini langsung bertumpu pada dinding keliling, sedangkan tepian atasnya ditopang blandar pada saka guru. Saka-saka tepi ini dihubungkan dengan balok-balok blandar dan sunduk. Di antara bangunan cungkup dan gapura dalam terdapat bangsal terbuka beratap cukup landai dengan penutup dari sirap kayu. Bangunan berdenah persegi 127 panjang dengan bubungan ke arah utara-selatan yang acapkali disebut sebagai Pendopo, Peziarahan atau Pasujudan ini adalah tempat para peziarah berdhikir dan memanjatkan doa dengan menghadap ke arah pintu cungkup di sebelah utara. Pasujudan ini adalah bangunan yang relatif baru lantaran dibuat pada tahun 1970-an dengan memanfaatkan kayu sawo yang sangat besar yang tumbuh di samping cungkup. Di sisi selatan gapura dalam terdapat bangunan persegi panjang yang menempel langsung pada sisi selatan gapura. Atap bagian atas bangunan serupa pendopo kecil yang kadang disebut sebagai Pasekaran ini ditopang saka guru yang diikat oleh blandar dan sunduk, sedangkan atap bagian bawah ditopang oleh pilar pasangan bata di keempat sudutnya. Dua kolom kayu berbentuk silinder dijumpai di bagian tengah sisi barat dan selatan bangunan ini. Ternyata kolom-kolom ini semula adalah saka guru masjid yang dipindahkan saat masjid tersebut diperbesar sehingga saka yang lama tak diperlukan lagi. Tepat di barat pendopo ini terdapat bangunan sangat kecil namun memegang peran penting dan memiliki artikulasi yang unik. Bangunan ini adalah Bale Pasalinan yang dipergunakan oleh para pengelola Kramat untuk berganti busana saat mereka akan mulai bertugas baik dalam rutinitas keseharian maupun saat upacara besar. Di bangunan ini juga disimpan beberapa benda yang diyakini memiliki kekuatan supranatural seperti bebebrapa tombak, bekas mustaka Masjid dan kuda lumping yang terbuat dari kulit. Meskipun sangat kecil bangunan ini memiliki artikulasi yangsarat dengan detail. Daun dan ambang pintu ini sarat dengan ornamentasi ukir di seluruh permukaan luarnya. Pintu yang sekarang terpasang ini didapat dari bekas pintu Kabuyutan yang diganti pada tahun 2010. Dinding Pasalinan yang relatif rendah ini dibagi dua. Bagian bawah terbuat dari pasangan bata sedangkan bagian atas terbuat dari anyaman bambu tutul yang artistik. 128 Gambar 4.10. Bale Pasalinan dan Batu Pendadaran 4.5.4. Masjid Masjid adalah bangunan yang terbesar di Kramat Buyut Trusmi. Beberapa sumber tertulis menyebutnya sebagai Masjid Sang Aji Rasa (Adimuryanto, 2001) mungkin untuk menunjukkan kedekatannya dengan Masjid Sang Cipta Rasa di Kraton Kasepuhan, Cirebon. Ruang Utama Masjid berdenah persegi dengan atap piramida bersusun tiga yang ditutup dengan sirap. Meskipun atap masjid ini bersusun tiga namun tiang penopangnya hanya empat yang terletak di sudut atap susun kedua. Atap teratas Masjid ini yang berhias mustaka tanah liat ditopang oleh balok-balok yang terentang di antara keempat tiang tersebut. Atap terbawah dipikul oleh dinding keliling. Semula bangunan Masjid ini lebih kecil dan jauh lebih rendah. Hal ini tampak dari pintu-pintu tuanya yang terletak di sisi utara dan selatan ruang shalat yang memiliki ketingian sekitar 1,5 meter. Bekas ketinggian dinding lama kurang 129 lebih setinggi lapisan batu paras pada dinding ruang dalam Masjid. Akan tetapi jejak ini sekarang sudah sepenuhnya terhapus ketika keseluruhan permukaan dinding ini dilapisi dengan keramik pada awal tahun 2015. Pada dinding sisi barat terdapat dua ceruk yang dipergunakan untuk mihrab dan mimbar yang diapit oleh dua jendela tinggi karena dibuat setelah bangunan Masjid ditinggikan. Gambar 4.11. Bangunan dan Ruang Dalam Masjid 130 Tepat di bagian timur Masjid ini terdapat dua struktur sang identik yang membentuk serambi. Struktur tengah serambi ini serupa dengan Witana namun bagian tepinya ditopang oleh dinding pemikul. Tak seperti lazimnya masjid Jawa yang memiliki serambi terbuka tanpa dinding, serambi Masjid Trusmi ini dibatasi oleh dinding rapat dengan beberapa jendela dari panil kayu. Dinding dan kedelapan saka serambi ini adalah yang tertinggi di Kramat Buyut Trusmi. Dalam amatan yang lebih cermat didapati bahwa tiang-tiang tersebut adalah sambungan. Penampang yang lebih lebar pada bagian bawah kolom terbentuk karena lapisan papan yang dipergunakan untuk menyambung bagian atas dan bagian bawah kolom. Gambar 4.12. Masjid dan serambi yang beratap sirap dan Pawadonan yang beratap alang-alang Di selatan ruang shalat utama terdapat ruang shalat perempuan atau Pawadonan. Bangunan yang juga tertutup ini dibongkar dan dibangun ulang saat perluasan Masjid di pertengahan tahun 1960an. Ruang shalat dan serambi Masjid memiliki penutup atap sirap sedangkan Pawadonan menggunakan penutup atap welit. Hal ini dilakukan mungkin karena Pawadonan ini sebelumnya juga dipergunakan sebagai tempat tirakat perempuan 131 sehingga menyandang peran sebagai Jinem Wadon. Dengan demikan dapat dipahami bahwa bangunan ini dibuat dengan bahan sebagaimana Jinem Wetan dan Kulon. Pada tahun 1990 fungsi tirakat ini diwadahi di Jinem Wadon yang dibangun secara khusus di sebelah barat Masjid. Bangunan tirakat ini serupa dengan Jinem dan Pawadonan dengan atap welit dan dinding pasangan bata. 4.5.5. Paseban Bangunan beratap welit dengan dimensi terbesar adalah Paseban yang terletak tepat di utara gapura barat. Bagian tengah bangunan ini ditopang oleh empat saka guru dengan dimensi 18 x 18 cm. Di atas saka guru terdapat balok-balok blandar yang besar berujuran sekitar 12 x 18 cm untuk mengikat keempat tiang tersebut dengan sistem konstruksi cathokan sehingga memiliki sisa balok di ujung (gimbal). Di bawah blandar terdapat sunduk atau balok-balok pengikat dengan purus di tiaptiap ujungnya. Di atas blandar terdapat susunan tiga lapis balok yang sarat dengan ornamern memahkotai ruang dalam bagian tengah ini. Ukiran tersebut sangat kontras bidang atap yang terbuat dari alang-alang tepat di atas susun balok ini. Sesanten atau balok pendek penghubung antara blandar dan sunduk berukuran besar berukir rumit dengan ganja di ujung atasnya. Kesemua elemen konstruksi Paseban tersebut membentuk ruang dalam yang termegah di seluruh kompleks Kramat Buyut Trusmi. Beberapa bidang kayu berukir tokoh wayang yang digantungkan pada langit-langit menambah kesan bahwa ruang ini memang diistimewakan. Dari luar, semua artikulasi canggih tersebut sama sekali tak kelihatan mengingat atap dan teritis yang relatif rendah. 132 Gambar 4.13. Paseban, Bale Kiai dan Bale Kunci (dari kiri ke kanan) Gambar 4.14. Struktur utama Paseban Tepat di timur Paseban terdapat dua bangunan serupa Bangunan yang menempel pada paseban adalah Bale Malang atau Bale Kiai tempat para Kiai berjaga dan beristirahat sehari-hari. Bale Kunci, tempat para Juru Kunci berjaga terletak 133 persis di sebelah timur Bale Kiai. Semua sisi bangunan tersebut tertutup oleh anyaman bambu kecuali sisi yang menghadap ke barat. Gambar 4.15. Bale Kiai dengan atap terbuka saat Memayu Secara tektonika kedua bale yang hampir sama ini memiliki keunikan. Struktur utama dengan empat tiang pada bale ini sama dengan yang dijumpai di Witana dan di bangunan lain, Akan tetapi bagian bawah kolom ini diikat oleh balok di keempat sisinya dengan konstruksi serupa sunduk dengan purus di ujungnya. Di atas balok-balok ini sejumlah papan disusun rapat sehingga membentuk amben atau balai-balai setinggi 50 sentimeter. Di seluruh Kramat hanya kedua bangunan ini yang memiliki konstruksi dan elemen seperti ini. Namun demikian, bukan berarti konstruksi sunduk-amben ini jarang dijumpai atau bahkan tidak dikenal di Trusmi. Pada rumah kuna yang dipusakakan seperti di Omah Gede dan beberapa Bale Gede konstruksi seperti ini selalu dijumpai terutama untuk bagian bangunan yang berada di depan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bangunan ini memiliki karakter domestik yang kuat. 134 4.6. Buka Sirap 4.6.1. Persiapan Buka Sirap Pada malam Senin tanggal 4 September tahun 2014 yang bertepatan dengan malam 1 Muharram 1435 H terjadi peristiwa penting di Trusmi. Malam itu bangunan Witana menyandang ulang peran sebagai tempat asal-muasal. Kiai Tonny selaku Sep menyampaikan maksud acara ini yakni mengumumkan jadwal penyelenggaraan upacara Buka Sirap untuk tahun 1435 yang kebetulan jatuh pada tahun Alip yang merupakan tahun pertama dari siklus windu delapan tahunan. Witana dengan demikian menyandang peran untuk “wiwitan” bagi rangkaian aktivitas terkait penggantian atap sirap kayu untuk sejumlah bangunan di Kramat Buyut Trusmi. Buka Sirap tahun 2014 ini adalah yang pertama kali dijalani Kiai Tonny selaku Sep menggantikan Kiai Ahmad yang meninggal pada tahun 2012. Acara utama melepas dan mengganti sirap dijadwalkan untuk dilaksanakan mulai hari Senin 8 September 2014 dan diakhiri pada hari Senin berikutnya tanggal 15 September 2014. Pada bulan Agustus mereka sudah mulai bekerja membuat sirap. Kayu jati untuk membuat sirap tersebut didapatkan dari tiga sumber, yakni: kayu jati yang ditanam sendiri oleh pengelola Kramat baik di sekitar makam atau di tanah wakaf lain yang berjarak sekitar 1 kilometer dari makam; kayu jati sumbangan dari warga; serta kayu jati yang dibeli oleh pengelola. Pembelian ini bisa dilakukan dengan dukungan dana sumbangan tunai dari warga atau kadang dengan menjual sumbangan non-tunai seperti binatang ternak yang berupa kerbau, sapi dan kambing, yang berlebih dari acara Buka Sirap empat tahun sebelumnya. Untuk tahun 1435 tersebut volume kayu yang diperlukan diperhitungkan mencapai sekitar 27 m3. 135 Gambar 4.16. Sirap dalam berbagai ukuran Sirap-sirap baru yang akan dipasang sudah ditumpuk di Witana. Bilah-bilah kayu dengan berbagai ukuran ini sudah dimandikan di Balong Pakulahan yang terletak tepat di timur bangsal kecil ini. Karena bangunan-bangunan di Kramat Buyut Trusmi dianggap suci maka komponen-komponen bangunan yang akan dipasang pun harus disucikan terlebih dahulu. Kolam berbentuk persegi ini dibuat dengan undakundakan di sisi barat sehingga memudahkan orang yang memasukkan komponen bangunan yang disimpan sementara di Witana, menyucikannya di air kolam dan terakhir mengangkatnya untuk disimpan di Witana atau langsung dipasang. 136 Gambar 4.17. Menyucikan sirap dan komponen konstruksi di Balong Pakulahan di samping Witana Gambar 4.18. Para pengobeng dan tukang menunggu Buka Sirap dimulai 4.6.2. Pelaksanaan Buka Sirap Senin pagi pukul 06.00 tanggal 8 September 2014 banyak orang sudah bersiaga di kompleks Kramat Buyut Trusmi. Para tukang membaur dengan para 137 pengobeng laki-laki duduk sejak matahari terbit siap untuk melakukan prosesi Buka Sirap. Mereka duduk atau berjongkok dengan pandangan terfokus pada bangunan Kabuyutan yang akan dikerjakan pertama kali mengawali prosesi ini. Sep, para kiai dan para kunci bergantian masuk ke Bale Pasalinan yang terdapat tepat di barat gapura barat menuju makam. Di bangunan mungil itu mereka mengganti pakaian biasa dengan baju, kain panjang dan ikat kepala yang semua bewarna putih polos. Menjelang pukul 07.00 kesembilan pengelola Kramat inipun siap untuk menaiki atap melalui tangga yang disandarkan di sisi timur bangunan makam. Kiai Tonny selaku Sep adalah orang yang naik pertama kali diikuti oleh para kiai dan kunci. Hanya sembilan orang ini yang boleh menaiki atap, memperbaiki bangunan dan mengganti komponen bangunan makam. Hal yang pertama kali mereka lakukan di atas atap adalah membersihkan atap dengan sapu lidi, melepas keping kaca yang ada di bagian atap yang akan diganti serta memasang beberapa batang reng di atap bagian atas sebagai pijakan untuk menuju ke puncak atap. Mereka bersembilan kemudian segera menuju ke bubungan untuk kemudian mengangkatnya. Bubungan yang terbuat dari kayu utuh ini sangat berat mungkin sekitar 100 kg sehingga diperlukan kesembilan orang ini untuk melepaskan bersamasama. Saat pengelola atap mulai naik tangga, para pengobeng dan tukang segera berdiri menandakan kesiagaan mereka untuk berkarya juga. Pada saat bubungan mulai dilepaskan, beberapa tukang menaiki kedua perancah tinggi yang didirikan di kiri dan kanan makam. Mereka menuju ke jajaran balok yang berfungsi sebagai lantai yang terletak pada ketinggian yang hampir sama dengan bubungan. Empat orang naik di tiap perancah untuk memegang dan mengendalikan kabel baja tempat bubungan akan digantungkan. Dengan tali plastik yang liat ujung-ujung bubungan tersebut diikat pada kabel baja yang terletak di bawah komponen bangunan yang paling dimuliakan ini. Para tukang menarik dan mengulur kabel-kabel tersebut agar bubungan tepat berada di atas balok bubungan dengan jarak ke atas sekitar 0,5 meter. Selama prosesi Buka Sirap berlangsung 138 bubungan ini akan tetap mengambang di atas bangunan. Seorang tukang bercerita bahwa di masa lalu sebelum menggunakan kabel baja, bubungan itu ditopang oleh balok-balok kayu yang dipasang bersilangan yang bertumpu pada rangka atap. Gambar 4.19. Melepas bubungan Kabuyutan dan meletakkannya di atas kabel baja yang ditopang perancah kayu Setelah bubungan diletakkan di atas kabel, kesembilan orang ini mulai melepas papan-papan bubungan jurai. Bubungan pada jurai di sudut tenggara adalah yang pertama kali dilepas. Dimulai dari bubungan jurai yang terpasang di atap bagian atas lalu diikuti dengan yang terpasang di atap bagian bawah. Ketika papan-papan yang sudah terlepas ini diturunkan, para pengobeng dan tukang berebut untuk membawanya ke luar halaman dalam makam. Keriuhan terjadi karena semua orang ingin mengambil bagian dalam pemindahan papan ini, paling tidak menyentuhnya sebagai upaya untuk menunjukkan keterlibatan dalam proses ini. Bersentuhan dengan papan-papan panjang dan berbagai komponen bangunan lainnya adalah syarat minimal untuk mengubah status mereka dari penonton menjadi pengobeng atau bahkan tukang. Papan-papan itu kemudian dikeluarkan melalui pintu gapura untuk kemudian diletakkan di halaman luar makam. Sebagian besar ditaruh di dekat Jinem Kulon. Papan-papan bubungan jurai Kabuyutan tersebut lebih panjang ketimbang 139 komponen serupa pada bangunan-bangunan lain. Dengan pemotongan pada bagian ujung yang biasanya lebih cepat keropos dan pengamplasan ulang permukaanya yang berkerak, papan-papn ini ssiap dimanfaatkan kembali. Gambar 4.20 pengobeng berebut menyentuh dan membawa keluar bubungan jurai yang telah diturunkan Semua bubungan jurai dilepas kecuali yang terletak di sudut barat laut karena memang bagian tersebut tidak berhubungan dengan penggantian sirap saat ini. Pada tahun 1435 ini hanya bidang atap di sisi timur dan selatan yang akan diganti penutupnya. Kemudian, berangsur-angsur keping-keping sirap penutup atap dilepas dan diturunkan. Beberapa di antara keping sirap tersebut selain digantungkan pada pengaitnya juga diperkuat dengan paku sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk melepasnya. Tiap kali setumpuk sirap diturunkan, orang-orang yang berjaga di bawah berebut untuk menerima dan kemudian secara beranting membawanya ke halaman luar makam. Prosesi ini berlangsung sepanjang siang hingga pukul 15.00 dengan dua kali waktu rehat untuk makan siang dan shalat dhuhur. Di akhir hari sebagian besar sirap makam dan semua bubungan jurai sudah selesai diturunkan. Di sekitar Jinem Wetan dan Jinem Kulon, bilah-bilah sirap ini ditumpuk dan diseleksi kelayakannya untuk dipasang kembali di bangunan lain. 140 Gambar 4.21. Memasang sirap baru di sisi selatan atap Kabuyutan Pada hari Selasa pukul 07.00 dimulai penggantian atap untuk bangunan Masjid. Keempat pengelola Masjid yakni Lebe beserta tiga stafnya, yakni, Kaum, Modin dan Merbot—kesemuanya berpakaian serba putih juga—menaiki atap Masjid melalui tangga yang dipasang di sisi utara tepat di atas pintu yang khusus dipergunakan oleh para Kiai. Beberapa orang ikut naik membantu para pengelola Masjid. Mereka memanjat atap Masjid yang bersusun tiga. Setelah mencapai puncaknya, mereka melepas mustaka atau hiasan puncak atap yang tebuat dari tembikar berbentuk seperti piramida dengan alas persegi dan hiasan ujung berbentuk seperti mahkota. Setelah dilepas, mustaka itupun diturunkan dengan menyungginya di atas kepala Lebe selaku pempinan tertinggi pengelola Masjid. Empat orang lain memegang semua sudut alas mustaka ini. Karena bagian tengah mustaka ini berongga maka kepala Lebe ini masuk ke dalam ceruk itu sehingga sulit untuk memandang sekeliling. Dengan menyunggi mustaka Lebe turun meniti tangga. Sesampainya di bawah, mustaka itu diletakkan pada batur pembatas pohon belimbing di utara Masjid. Setelah diperiksa dan dibersihkan, mustaka tersebut dicat 141 ulang dengan warna merah tua. Hiasan puncak atap ini disemayamkan di dalam Masjid sesudah kering catnya. Gambar 4.22. Penurunan mustaka Masjid yang disunggi Lebe Bubungan jurai dan sirap Masjid kemudian dilepas dan diturunkan sebagaimana yang dilakukan pada atap Kabuyutan. Dimulai dari atap ruang shalat dan dilanjutkan kemudian dengan atap Witana dan Bale Pasalinan. Setelah dilepas, komponen-komponen tersebut juga dibawa ke halaman depan Makam. Pada hari ketiga Buka Sirap yang selalu jatuh pada hari Rabu dilakukan penggantian atap pada atap semua gapura. Bangunan-bangunan kecil ini memang sebelumnya tidak beratap sirap sehingga mendapat perlakuan yang berbeda. Hampir semua sirap untuk gapura-gapura ini adalah sirap bekas yang masih layak dan sudah dibersihkan sehingga tampak seolah-olah baru. Bangunan di depan Kabuyutan yang sering dipergunakan untuk para peziarah bertafakur dan berdoa mendapat perlakuan yang berbeda pula. Bangsal yang dianggap baru dan tambahan ini hanya diganti bubungan jurainya, sedangkan atap sirap di keempat sisinya tak diganti. Penggantian komponen bangunan ini dipandang sebagai perbaikan teknis sehingga dilakukan sejauh memang ada kerusakan dan 142 tersedia komponen pengganti bekas dari bangunan lain. Dalam Buka Sirap kali ini bubungan jurai pengganti didapat dari bekas bubungan jurai Kabuyutan. Gambar 4.23. Menurunkan sirap dan bubungan jurai sisi timur Masjid Gambar 4.24. Mengganti atap sisi timur Witana 143 Bangunan terbesar yang mulai dikerjakan pada hari Rabu adalah serambi Masjid. Bangunan yang dinaungi oleh dua atap berjajar ini memerlukan penanganan teknis yang cermat karena banyaknya lekuk liku dan sambungan atap. Sementara, bubungan dan sirap bekas yang telah ditumpuk di halaman depan tersebut diperiksa kondisinya. Setelah diseleksi dapat disisihkan komponen yang sudah tak layak untuk dipakai lagi karena sudah terlalu banyak bagian yang keropos atau lapuk. Beberapa orang mengambil sirap-sirap bekas ini untuk dibawa pulang karena nilai berkahnya. Banyak komponen memerlukan perbaikan dan penyesuaian untuk dapat dipakai kembali. Hampir semua sirap dan bubungan jurai dari Kabuyutan masih bisa dipakai kembali mengingat setiap kali Buka Sirap semua komponen yang dipasang di bangunan ini haruslah komponen baru kecuali bubungan yang dibuat secara khusus dari kayu gelondongan yang hanya digantungkan untuk kemudian dipasang kembali. Keping-keping sirap yang masih baik memerlukan pengamplasan pada permukaannya untuk menghilangkan jamur dan lumut yang dengan cepat tumbuh. Bubungan atas dan bubungan jurai yang masih dapat dipergunakan memerlukan penyesuaian ukuran dengan bangunan baru tempat komponen tersebut akan dipasang. Pemendekan ini perlu dilakukan karena ukuran Kabuyutan yang lebih besar dari pada bangunan lain sehingga memiliki bubungan jurai yang lebih panjang juga. Selain itu, pemendekan juga dilakukan karena alasan kualitas komponen bangunan lantaran ujung-ujung bubungan biasanya adalah bagian yang paling mudah lapuk sehingga perlu dipangkas. 144 Gambar 4.25. Kiai Warlan menyeleksi sirap baru untuk Kabuyutan Pada hari keempat atau hari Kamis semua pekerjaan perbaikan dan penggantian atap tersebut dilanjutkan. Bubungan jurai yang baru sebelum buka sirap dimulai disediakan dalam bentuk papan-papan sepanjang tiga meter yang belum disesuaikan ukurannya dengan komponen bangunan yang akan diganti. Sesudah pembongkaran baru diketahui bubungan jurai mana saja yang memerlukan penggantian komponen baru. Ujung bubungan jurai yang tersambung dengan bubungan jurai di bawah atau di atasnya memerlukan ketelitian dalam pemotongannya mengingat kemiringan masing-masing atap berbeda. Banyak pekerjaan penyesuaian dilakukan pada hari itu. Semua aktivitas teknis pembaruan bangunan pada Buka Sirap dihentikan pada hari Jumat. Jeda ini ditujukan untuk menghormati hari yang dikhususkan untuk melaksanakan ibadah Shalat Jumat. Keesokan harinya pada hari Sabtu aktivitas Buka Sirap difokuskan untuk merapikan dan menyempurnakan konstruksi. Pemasangan bubungan jurai dengan lapisan ijuk di bawahnya, misalnya memerlukan kecermatan khusus agar tampil rapi dan tidak bocor. Pada hari Sabtu sore kesemua pekerjaan pengakhiran inipun usai 145 kecuali bubungan utama Kabuyutan dan mustaka Masjid yang masih harus menunggu saat yang tepat secara ritual untuk dapat dipasang kembali ke tempat semula. 4.6.3. Akhir Buka Sirap Hari Ahad adalah hari persiapan kenduri syukuran usainya Buka Sirap. Semua pengobeng sibuk untuk mengelola penyiapan makanan yang akan didistribusikan pada saat kenduri. Pada malam hari kembali dilaksanakan tahlilan di depan Kabuyutan dan Shalawat Brai, kali ini satu kelompok saja, dipentaskan di halaman depan makam. Keesokan harinya sebelum jam 06.00 kenduri besar untuk mensyukuri usainya Buka Sirap telah siap. Hidangan berkat untuk para tokoh masyarakat dipersiapkan di dua tempat. Para pengelola Kramat dan tokoh-tokoh formal seperti Kuwu Trusmi Wetan dan Kulon serta Muspika Weru dipersilakan untuk duduk di Paseban sedangkan para tokoh informal duduk di Witana. Sekitar pukul 05.55 Sep beserta keempat Kiai dan keempat Kunci kembali naik ke atas bangunan Kabuyutan untuk mulai melakukan prosesi konstruksi sekaligus ritual untuk menandai pengakhiran Buka Sirap. Beberapa tukang memanjat perancah tinggi yang ada di kiri dan kanan bangunan tersebut. Tukang-tukang tersebut melonggarkan kabel baja yang dipergunakan untuk mengangkat bubungan Makam. Para pengelola Kramat bersiaga di atas atap untuk mengepaskan posisi bubungan tersebut pada tempat kedudukannya. 146 Gambar 4.26. Memasang kembali bubungan dan membersihkan atap Kabuyutan Setelah bubungan terpasang dilakukan penanganan teknis terakhir. Dengan mesin pengamplas beberapa pengelola kramat menghaluskan kembali permukaan bubungan serta menghilangkan kerak, lumut dan jamur yang menempel di permukaannya. Satu-satunya komponen lama yang dipasang ulang di Kabuyutan inipun tampil seperti baru. Prosesi ritual dilakukan kemudian. Setelah seluruh permukaan atap dibersihkan dengan sapu lidi, tiga untai melati dengan aksen mawar merah di ujungnya disangkutkan di atas bubungan menjadi penanda usainya Buka Sirap. Terakhir, dua orang Kunci memercikkan air sambil berjalan berkeliling di atas atap bagian bawah sehingga seluruh permukaan atap mendapat percikan air tersebut. Pada saat yang bersamaan dengan pengakhiran Buka Sirap di Kabuyutan dilakukan hal yang sama di Masjid Kramat Buyut Trusmi. Lebe bersama ketiga stafnya dan dua orang tukang naik ke atap Masjid. Kali ini Lebe kembail menyunggi mustaka Masjid di atas kepalanya. Sesampainya di puncak atap, mustaka inipun dipasang kembali menghiasi puncak masjid. 147 Setelah pekerjaan teknis usai dilakukan, ritual pengakhiran dimulai. Setelah untaian melati dipasang untuk menghiasi puncak bangunan Masjid ini, Modin segera memegang mikrofon dengan berdiri di atap Masjid. Pukul 06.33 hari Senin adhan diserukan dari puncak Masjid Kramat Buyut Trusmi bukan untuk menyerukan waktu shalat tapi untuk mempermaklumkan usainya pembaruan kembali bangunan Masjid melalui prosesi Buka Sirap. Gambar 4.27. Modin menyerukan adhan di puncak Masjid seusai pemasangan mustaka Distribusi berkat yang paling banyak dilakukan di depan Masjid. Para pengobeng yang telah duduk menunggu di halaman masjid mendapat giliran pertama untuk mendapatkan berkat yang diwadahi dalam ponthang. Ribuan orang yang telah menunggu di Alun-alun dengan tertib mengantre di depan gapura timur untuk kemudian menerima berkat di depan masjid. Sebelum pukul 10.00 perhelatan besar delapan hari ini usai. Karena tahun 1435 jatuh pada tahun Alip, maka dilakukan juga Buka Sirap untuk mengganti atap bangunan Mande Cungkup Trusmi yang terletak di Astana atau Kompleks Makam Sunan Gunungjati di Bukit Sembung sekitar 4 kilometer dari Trusmi. Prosesi ini mulai dilaksanakan pada hari Ahad sore sepekan setelah Buka Sirap di Kramat Buyut Trusmi. Bersama-sama, orang-orang Trusmi membawa sirap ke Astana tersebut. Di malam harinya diselenggarakan pertunjukan wayang kulit di 148 halaman dekat Mande Trusmi untuk memeriahkan prosesi ini. Senin pagi tanggal 22 September 2014 dimulailah penggantian sirap untuk bangunan yang menandai pertalian antara warga Trusmi dan dinasti Gunungjati. 4.7. Memayu 4.7.1. Persiapan Memayu Memayu atau penggantian atap welit pada bangunan-bangunan di Kramat Buyut Trusmi hanya memakan waktu satu hari. Namun demikian, hubungan antara aspek teknis, ritual dan sosial dalam Memayu tidak kalah kompleks dibandingkan dengan Buka Sirap yang memakan waktu hingga delapan hari. Saya menyaksikan dan terlibat dalam Memayu yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2014 dan 28 September 2015. Kedua upacara tersebut ternyata jatuh pada tahun Hijriyah yang sama yakni 1436 Ehe. Sebagaimana Buka Sirap, saat pelaksanaan Memayu juga diumumkan pada malam tanggal 1 Muharram dalam majelis yang diselenggarakan di Witana. Pertimbangan dalam menentukan saat penyelenggaraan Memayu memang kompleks. Prosesi ini selalu dijadwalkan pada hari Senin. Berdasar perhitungan tradisional (hisab ‘urfi) mereka didapatkan ancar-ancar tanggal pelaksanaan upacara ini dalam kalender Hijriyah. Memayu dipandang berkaitan erat dengan ritus pertanian untuk mengawali masa tanam padi yang dilakukan pada awal musim penghujan. Selain tarikh Hijriyah dan perhitungan awal musim hujan, jadwal Memayu juga perlu untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kedua upacara ini dapat terselenggara dengan dukungan sumbangan yang besar dari masyarakat. Jika jarak antara Memayu dan Buka Sirap terlalu dekat maka dikhawatirkan akan menjadi beban yang terlalu berat bagi masyarakat. Persiapan teknis untuk memayu yang paling penting adalah pengadaan welit atau alang-alang (Imperata cylindrica) yang dirangkai pada bilah bambu sepanjang sekitar 1,5 meter. Alang-alang ini tidak tumbuh di Trusmi sehingga harus dipesan di kawasan pesisir tepatnya di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu. Paling tidak tiga 149 bulan sebelum pelaksanaan Memayu, welit tersebut harus sudah dipesan. Sekitar seminggu sebelum Memayu, welit tersebut mulai didatangkan. Semula welit itu ditumpuk di ruang terbuka atau di Jinem Wetan dan Kulon, tapi mulai tahun 2015 welit tersebut disimpan di bangunan permanen berdinding bata yang didirikan di sisi timur Alun-alun Trusmi. Bangunan ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan sirap, kayu jati dan alat-alat pertukangan yang dipergunakan dalam Buka Sirap. Bahan lain yang diperlukan adalah bambu dan anyaman belarak atau daun kelapa kering. Bambu diperlukan untuk dibuat sebagai tali pengikat dan bilah penjepit. Anyaman belarak dipasang di tepi teritis bangunan untuk merapikan pinggir atap tersebut. Kedua bahan ini bisa didapatkan di beberapa desa di Kecamatan Weru. Pada hari Ahad, sehari sebelum pelaksanaan Memayu, diselenggarakan pawai besar yang disebut sebagai ider-ideran. Arak-arakan ini berangkat dari Kramat Buyut Trusmi menuju Jalan Syeh Datu Kafi—Jalan Raya Cirebon-Bandung—Jalan Panembahan Ratu dan kembali ke Kramat. Para peziarah khususnya yang dari luar kota justru datang paling banyak pada saat Ider-ideran ketimbang saat pelaksanan Memayu di keesokan harinya. Sekumpulan benda yang didistribusikan kepada peziarah saat Memayu yang diyakini memiliki nilai berkah ini adalah lidi, minyak goreng, abu dan beberapa bulir benih padi atau gabah. Secara khusus, abu tersebut didapatkan dari sisa-sisa pembakaran kemenyan yang dilakukan setiap hari di Kabuyutan. Kiai Tonny menfasirkan secara filosofis makna benda-benda tersebut. Lidi yang lurus dimaknai sebagai tauhid atau pengakuan keesaan Allah. Minyak yang bersifat licin dikaitkan dengan harapan akan kemudahan segala urusan, sedangkan gabah adalah ungkapan harapan akan kesejahteraan. Abu adalah pengingat bahwa kita semua akan kembali sebagai abu. Kiai Warlan, tokoh yang lebih senior, memiliki pemahaman tentang bendabenda yang dibagikan tersebut yang sangat terkait dengan asal-muasal Memayu sebagai ritus pertanian. Gabah jelas adalah benih padi yang akan disemai di awal musim tanam. Abu, menurutnya, adalah pupuk untuk menyuburkan lahan. Lidi biasa 150 ditancapkan di sudut-sudut sawah untuk menolak hama. Minyak dihubungkan dengan tenaga kerja manusia yang mengolah sawah mengingat usai bekerja sering pegalpegal maka dipergunakanlah minyak untuk mengurut. Di menjelaskan lebih lanjut bahwa arti penting Memayu bagi masyarakat petani di Trusmi adalah untuk mengumpulkan sanak-kerabat dan tetangga untuk bersiap menyambut musim tanam padi. Sebelum pukul 05.00 para peserta arak-arakan sudah bersiaga, penontonpun sudah ramai memadati sepanjang jalan yang akan dilewati oleh arak-arakan ini. Para pengelola Kramat pagi itu sudah siap dengan memakai baju putih dengan ikat kepala dan sarung batik yang seragam. Satu kelompok yang terdiri atas dua belas Kemit menyandang tombak, tiga kelompok lainnya membawa ujung tanaman bambu sepanjang sekitar tiga meter yang masih lengkap dengan daun-daunnya. Batang bambu melengkung yang dibawa para kemit ini masih segar sehingga dapat menimbulkan gambaran tentang makna Trusmi sebagai Terus Semi. Seorang tokoh setempat menjelaskan bahwa bambu tersebut lebih penting ketimbang tombak sehingga semestinya semua Kemit tersebut membawa bambu. Akan tetapi, para Kemit yang hari itu bertugas piket di Kramat tidak punya kesempatan untuk mencari bambu, maka mereka membawa tombak yang memang sudah tersedia di Kramat. Pukul 06.00, dengan sambutan pendek dari Camat Plered, parade Ider-ideran ini pun diberangkatkan. Lebih dari lima ratus partisipan mengambil bagian dalam arak-arakan, sedangkan ribuan lainnya menonton di pinggir jalan. Secara umum, peserta Ider-ideran terdiri atas tiga kategori. Pertama adalah peserta arak-arakan yang bersifat ritualistik dengan keterkaitan kuat dengan simbolisme dan aktivitas di Kramat. Kedua, peserta arak-arakan yang menunjang ritual khususnya yang bertugas untuk membuka jalan dan mengamankan upacara. Ketiga, partisipan yang memeragakan kebolehan, kecakapan dan kemampuan mereka untuk dipertontonkan sepanjang kalan. 151 Arak-arakan yang bersifat ritualistik semua diberangkatkan dari Kramat Buyut Trusmi. Setelah berhimpun dan menata barisan depan Paseban atau di belakang Kuta Hijab gapura barat parade ini berangkat dengan dua orang kemit berjalan paling depan membawa ukup atau tungku tanah liat besar untuk membakar kemenyan yang senantiasa mengepul sepanjang jalan. Tiga belas pengelola Kramat menyusul di belakangnya bersama Muspika dan Kuwu yang diikuti oleh empat puluh enam Kemit yang menyandang bambu dan lembing. Sekelompok orang yang berpakaian merah jambu berjalan berikutnya dengan jarak agak renggang. Masingmasing memikul sebatang bambu dengan empat welit diikatkan di ujung-ujungnya. Gambar 4.28. Bagian ritualistik Parade Ider-ideran (menurut arah jarum jam: Para pengelola Kramat; para Kemit menyandang bambu melengkung (atas), para pembawa welit (tengah) dan para pembawa pikulan hasil bumi yang dijarah saat berangkat dalam Ider-ideran Kiai Warlan meyakini bahwa asal-muasal Ider-ideran ini adalah mengarak welit yang akan dipasang pada saat Memayu keesokan harinya. Dengan 152 mempertontonkan welit sepanjang jalan, masyarakat sekitar akan tahu bahwa upacara penggantian welit segera akan dilaksanakan, sehingga mereka menyiapkan diri untuk berpartisipasi. Bagi peziarah yang datang dari tempat yang jauh, sekarang Ider-ideran telah berubah menjadi upacara utama yang wajib mereka hadiri sedangkan Memayu menjadi seperti antiklimaks dalam prosesi ini sehingga mereka tak lagi merasa perlu mengikuitinya. Setelah barisan pembawa welit menyusul para remaja laki-laki dan perempuan yang berhias rupawan dengan membawa tombak pendek menyajikan tari Babakan Yaso yang dipahami sebagai tari perjuangan setempat. Paling belakang dari arak-arakan ritual ini adalah sejumlah laki-laki yang membawa pikulan dengan nyiru yang ditumpangkan di atas bakul menggantung di kedua ujungnya. Pikulan ini sarat dengan simbol-simbol agraris. Beberapa jenis dedaunan dan bebungaan diikatkan pada tali pikulan tersebut sedangkan nyiru diisi dengan gabah dan buah-buahan. Begitu para pemikul ini melangkah mengikuti prosesi, orang-orang segera berebut untuk mendapatkan segenggam gabah, sebatang ranting atau setangkai daun yang diyakini membawa berkah. Dalam jarak 20 meter dari tempat keberangkatan, pikulan ini sebenarnya sudah nyaris kosong. Peserta yang paling banyak adalah mereka yang ingin menampilkan kebolehan tertentu dalam arti yang sangat luas. Dengan menunjukkan ketrampilan, keberanian, kecantikan atau bahkan kekonyolan mereka berpartisipasi dalam prosesi ini. Sekitar pukul 07.30 barisan terdepan Ider-ideran sudah kembali ke Kramat. Mereka langsung membubarkan diri. Beberapa orang meminta bambu panjang yang dibawa para Kemit untuk dibawa pulang. Sarapan di atas piring seng dihidangkan merata bagi semua mengakhiri parade ini. 4.7.2. Pelaksanaan Memayu Keseluruhan aktivitas untuk membongkar atap welit, mempersiapkan bahan dan memasang atap baru dalam Memayu selesai dalam setengah hari. Senin pukul 153 05.30 orang-orang Trusmi sudah bergegas menuju Kramat. Para lelaki mempersiapkan welit dan bambu, para perempuan menuju dapur di sudut barat laut Kramat untuk mulai memasak. Pada Memayu 2015, karena bangunan gudang di timur Alun-alun sudah difungsikan, semua orang pertama kali menuju ke sana untuk mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Pada saat itu welit pada sisi selatan dan timur diganti sedangkan pada tahun 2014 dilakukan penggantian welit terhadap atap di sisi utara dan barat. Prosesi Memayu lebih sederhana ketimbang Buka Sirap. Memayu terdiri atas dua aktivitas utama yang berjalan simultan yakni penurunan welit lama dan pemasangan welit baru. Penurunan welit dimulai pertama-tama di kluster bangunan Paseban, Bale Kiai dan Bale Kunci. Sebelum penurunan welit di kluster ini usai, welit di Jinem Kulon dan Jinem Wetan di depan Kabuyutan mulai diturunkan. Setelah keduanya hampir usai welit di Bale Keprinci, Pawadonan Masjid dan Jinem Wadon diturunkan. Prosesi untuk menurunkan welit dimulai dengan menurunkan welit yang menutup jurai oleh sekelompok orang yang memanjat atap di dekat sudut yang dibongkar pertama kali. Tali-tali bambu pengikat bambu panjang yang menjadi rangka welit diretas dengan parang dan rangkaian alang-alang yang melilit pada bambu itupun ditarik oleh merek yang berada di atas atap. Setelah semua bubungan jurai terlepas maka dimulailah untuk melepas atap welit. Pelepasan ini dilakukan dengan cara mencopot rangken atau bidang rangka bambu berbentuk segitiga atau trapesium tempat welit diikat. 154 4.29. Menurunkan welit dengan rangken dari Bale Kunci Setelah dilepas, rangken segera ditegakkan di tanah. Para pengobeng dengan sigap melepaskan welit-welit yang melekat pada rangken tersebut dengan meretas tali-tali bambu yang mengikat batang-batang bambu perangkai alang-alang dengan rangken. Tiga bangunan yang ada di sudut barat daya yakni Pawadonan Masjid, Jinem Wadon dan Bale Keprinci memiliki konstruksi yang berbeda. Pada ketiga bangunan ini welit dipasang langsung pada reng menempel di usuk tanpa menggunakan rangken. Untuk melepasnya, cukup dilakukan dengan meretas tali pengikat welit pada reng. Kiai Warlan menerangkan tentang alasan ketiga bangunan ini memiliki konstruksi yang berbeda lantaran ketiganya dianggap sebagai bangunan baru. 155 Gambar 4.30. Pelepasan welit tanpa rangken dari Bale Keprinci Sementara welit yang telah usang dilepas dari bangunan, welit baru dipersiapkan. Pertama kali yang ditangani adalah batang-batang bambu yang masih bewarna hijau yang dijajarkan di tanah lapang Alun-alun Trusmi. Bambu tersebut dipotong dalam tiga ukuran panjang. Batang dengan panjang sekitar 4 meter dibelah menjadi delapan bilah untuk dipergunakan sebagai bilah penjepit bagian bubungan jurai. Beberapa batang dengan panjang 4 meter dibiarkan utuh untuk membantu merakit welit untuk bubungan tersebut. Batang dengan panjang 1 meter dan 40 sentimeter dibelah halus menjadi setebal kurang dari 0,5 sentimeter. Belahan halus ini dipergunakan untuk tali pengikat welit. Alang-alang dibeli dari Desa Singaraja di Kabupaten Indramayu dalam bentuk welit. Alang-alang ditata rapat pada bilah bambu selebar 2 sentimeter dengan panjang sekitar 150 sentimeter. Pangkal alang-alang ditekuk pada bilah bambu tersebut dengan menyisakan daun yang menjuntai sepanjang 60 sentimeter. Tekukan ini diperkuat dengan penjepit sepasang bilah bambu yang lebih kecil selebar kurang dari 1 sentimeter. Kedua bilah ini diikat kencang dengan tali yang berjarak sekitar 5 sentimeter. 156 Untuk membuat bubungan, dua deret welit yang disusun rangkap dua digabung dengan mengikat batang bambu yang menjadi rangka utama welit tersebut. Masing-masing deretan welit dijepit oleh dua pasang bilah bambu sepanjang empat meter tersebut. Dengan demikian, untuk membentuk satu bubungan diperlukan dua belas welit dan delapan bilah bambu. Semua ikatan tersebut mempergunakan tali bambu pendek. Gambar 4.31. Membuat bubungan welit Welit untuk penutup atap, baik yang dpasang pada rangken maupun yang dipasang pada batang reng dipersiapkan dengan cara yang sama. Pada welit tersebut dipasang tali-tali bambu dengan jarak sekitar 10 sentimeter yang kemudian dipergunakan untuk mengikat welit pada rangkanya. Pemasangan welit pada rangken dilakukan di dekat bangunan yang akan diganti atapnya. 157 Gambar 4.32. Pemasangan welit pada rangken di Jinem Gambar 4.33. Pemasangan rangken di Jinem Wetan Segera setelah rangken diturunkan dari atap, welit lama dilepas untuk kemudian dilakukan pemasangan welit baru. Pemasangan welit dilakukan dari sisi bawah rangken berurutan ke atas dengan jarak sekitar 10 sentimeter. Welit ini diikat 158 pada rangken dengan tali bambu yang sudah dipasang sebelumnya sehingga membentuk tumpukan 4 sampai 5 lapis. Sesudah seluruh permukaannya tertutup welit, rangken tersebut dinaikkan ke atas rangka atap yang diperkuat dengan mengikatkannya pada usuk dan gelagar. Pada bangunan-bangunan yang tidak menggunakan rangken, welit-welit tersebut diikatkan dengan cara yang sama pada reng yang tertata di atas usuk. Sebagian dari welit lama ini dibawa pulang oleh para pengobeng untuk berbagai keperluan. Kiai Tonny menyebut manfaat welit ini antara lain untuk kesuburan lahan, menyembuhkan penyakit serta menolak bala dan guna-guna. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkannya secara langsung maupun membakar alangalang tersebut lebih dahulu baru abunya dipergunakan untuk berbagai keperluan tersebut. Setelah semua rangken dan welit terpasang, dilakukan pemasangan welit untuk bubungan dan bubungan jurai. Saat pemasangan, di bawah bubungan tersebut diganjal dengan alang-alang yang diikat seperti bundelan yang berjajar rapat di bawah bubungan. Bubungan, rangken dan bundelan tersebut dipasang dengan tali bambu yang panjang. Untuk merapikan tepian atap, setelah semua rangken dan bubungan terpasang dilakukan pemasangan anyaman belarak atau daun kelapa kering. Dua anyaman belarak selebar 30 sentimeter disatukan dengan dijepit oleh sepasan bilah bambu di tiap tepinya. Anyaman belarak yang telah dijepit ini dipasang di atap bagian paling bawah. Selain untuk merapikan, pemasangan belarak ini juga ditujukan untuk merapatkan atap mengingat pada bagian tersebut welit yang terpasang hanya satu dan dua lapis saja. Pada bangunan yang tidak menggunakan rangken, belarak tersebut justru dipasang pertama sebelum welit untuk menjadi patokan bagi pemasangan welit pada reng. Pada saat adhan dhuhur berkumandang, prosesi pembaruan atap welit inipun usai. Semua pengobeng makan bersama dengan menikmati makan siang yang telah 159 tersaji di atas ancak atau anyaman bambu berbentuk persegi untuk mewadahi nasi dan kelengkapannya untuk empat orang. Memayu tampaknya memang ritual yang sangat egaliter sebagaimana kelihatan pada saat makan bersama tersebut. Sepanjang prosesi, para pengelola Kramat sangat sedikit mengambil bagian kecuali mengatur lalu lintas logistik. Sejak sehari sebelum Ider-ideran masyarakat telah ramai mengantarkan bahan mentah,makanan, kudapan dan buah-buahan atau apa saja yang diperkirakan menjadi kebutuhan logistik Memayu. Sepulangnya dari mengantarkan sumbangan, mereka akan mendapatkan ketupat yang terbuat dari beras dan lepet yang terbuat dari beras ketan dari Kramat yang disampaikan oleh para Kemit. Satu-satunya bangunan beratap welit yang tidak diganti atapnya di Kramat Buyut Trusmi adalah bangunan dapur yang terletak di utara Paseban. Pada hari itu dapur tersebut masih dipergunakan untuk memasak hidangan untuk menunjang pelaksanaan Memayu. Karena hal tersebut, penggantian welit bangunan ini ditunda beberapa hari sesudahnya. Memayu atau penggantian atap alang-alang dilakukan di beberapa tempat di sekitar Kramat Buyut Trusmi dengan berbagai relasi. Memayu dilaksanakan di Omah Gede Trusmi, Bale Gede Bangbangan dan Bale Gede Kiai Warlan dengan cara yang sama namun dengan skala yang lebih kecil. Dua Bale Gede yang lain sudah tidak beratap alang-alang sehingga tidak dilakukan penggantian atap. Masyarakat sekitar juga berkontribusi dengan cara yang sama. Sumbangan makanan, bahan mentah dan uang tunai berdatangan. Tak jarang ada donatur yang menyumbang pentas wayang untuk memeriahkan acara pada malam sebelum pelaksanaan Memayu di tempat-tempat tersebut. Jadwal pelaksanaan Memayu berkaitan dengan klaim senioritas yang disepakati. Omah Gede yang diyakini dibangun oleh Ki Gede Trusmi, murid paling senior Ki Buyut Trusmi, mendapat jadwal pertama. Hari Kamis segera setelah Memayu di Kramat dilakukan upacara yang sama di Omah Gede. Memayu di kedua 160 Bale Gede lainnya dilaksanakan hari Senin sepekan setelah Memayu di Kramat Buyut Trusmi. 4.8. Pemugaran dan Pengembangan Bangunan Tak-Berkala Saat saya mengunjungi Trusmi untuk mengamati dan berpartisipasi dalam Memayu tahun 2015 terjadi perubahan yang cukup kentara. Sebuah outdoor unit perangkat pengkondisian udara (air-conditioner) tampak menonjol pada dinding barat masjid. Perangkat ini terhubung dengan indoor unit yang terpasang di atas jendela di samping mihrab. Permukaan dalam dinding Masjid dilapisi dengan keramik berukuran 60 x 60 sentimeter dengan warna coklat muda sedangkan bagian atasnya berpelisir ukiran kayu selebar sekitar 15 sentimeter yang menerus di keempat sisi ruang shalat tersebut. Kayu ini berukir kaligrafi berlanggam thuluth dengan pengerjaan yang baik yang menorehkan 99 nama Allah atu al-asma al-husna. Kiai Tonny menerangkan bahwa dirinya juga tak banyak menentukan perubahan ini karena penambahan AC, keramik dan ukiran kayu tersebut dilakukan atas prakarsa seorang donatur. Seorang kemit yang saya tanyai perihal penambahan sejumlah komponen baru di Masjid menyebutnya sebagai “paketan”. Istilah ini dimaksudkan untuk menyebut bantuan dari pihak luar yang berwujud barang sekaligus pemasangannya sehingga tidak melibatkan para pengelola Kramat maupun masyarakat setempat. Sep Tonny menambahkan ada juga pembaruan yang dilakukan atas inisiatifnya. Dia menunjukkan lantai berundak pada gapura barat dan gapura timur kompleks Kramat Buyut Trusmi. Di gapura timur latai berudak itu ditinggikan levelnya dari lantai semula untuk menanggulangi luapan air dari luar saat hujan deras. Konsekuensinya keseluruhan struktur gapura harus dinaikkan. Lantai itu juga dilapis dengan mosaik yang memiliki barik atau tekstur permukaan agak kasar sehingga lebih aman untuk diinjak saat hujan. Gapura barat hanya dipasangi mosaik saja tanpa perubahan ketinggian muka lantai. 161 Selain pembaruan atap secara berkala sebagaimana dilakukan dalam prosesi Memayu dan Buka Sirap, di Trusmi dilakukan juga pemugaran tak-berkala seperti pembaruan di Masjid dan gapura tersebut. Kwanda (2013) menyebut kedua aktivitas tersebut sebagai periodic renewal dan non-periodic renewal. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda (Kwanda, 2013: 122) yakni: Periodic renewal dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kosmis untuk memperbarui keselarasan dengan alam semesta dan memohon berkah kepada Yang Mahakuasa. Non-periodic renewal dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis yang karena prakarsa internal sebagai upaya perbaikan fisik ataupun prakarsa eksternal karena ketersediaan material dari donatur. Dengan amatan yang lebih seksama dan investigasi yang lebih mendalam, dijumpai pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks dalam melakukan pemugaran baik yang berupa perbaikan, pembaruan, pengembangan dan pembuatan bangunan atau bagian-bagian bangunan di Kramat Buyut Trusmi. Pemugaran ini dapat dilakukan bersamaan dengan momen Buka Sirap atau Memayu atau dilakukan secara mandiri. Sebagai suatu proses yang bersifat non-periodik, tiap pemugaran tersebut bersifat unik dan dapat diposisikan dalam konteks waktu tertentu. Dalam beberapa hal, pemugaran non-periodik ini dapat dipahami dalam kerangka diakronik yang mendudukkan masing-masing peristiwa dalam runtun waktu tertentu. 4.8.1. Perkembangan Awal Catatan sejarah Trusmi sangat minim karena bagi mereka akurasi dokumentasi suatu peristiwa dengan tujuan membangun relasi yang relatif mapan dengan peristiwa lain yang sejaman tampaknya tak dipandang penting. Siapa pengikut Ki Buyut Trusmi yang menjadi pemimpin pada beberapa generasi sepeninggal Sang Pendiri tak pernah digambarkan dengan jelas. Jika sang tokoh cikal bakal ini dipercaya meninggal di awal abad ke-16, warga setempat tak memiliki 162 catatan ataupun ingatan komunal tentang siapa yang memimpin Kramat dan Desa Trusmi selama empat abad berikutnya. Sejarah tokoh yang bersifat terfragmentasi ini jelas berdampak juga pada pengisahan sejarah arsitektur. Beberapa tokoh meyakini bahwa yang tinggal di Omah Gede adalah Ki Gede Trusmi, pengganti pertama Ki Buyut Trusmi. Akan tetapi, ketika saya konfirmasikan hal ini kepada penjaga Omah Gede dia menjawab bahwa mungkin Ki Gede Trusmi adalah orang yang berbeda dengan Ki Buyut Trusmi tapi mungkin juga keduanya adalah orang yang sama. Dengan demikian apakah Omah Gede adalah kediaman pemuka Trusmi setelah kediaman Ki Buyut Trusmi berubah menjadi Kramat ataukah rumah kuna ini adalah kediaman ketika kompleks Kramat Buyut Trusmi masih berperan sebagai pusat lingkungan Trusmi dan belum menjadi kubur tempat peziarahan mungkin juga tak akan dapat dijelaskan secara lebih konkret dan akurat. Meskipun terdapat variasi yang sangat besar tentang sejarah Kramat Buyut Trusmi, tetapi semua narasumber setempat bersepakat bahwa kompleks ini semula adalah kediaman Ki Buyut Trusmi yang kemudian berubah menjadi makam dan tempat peziarahan sepeninggal tokoh ini. Berangsur-angsur kegiatan peziarahan ini mendominasi aktivitas d kompleks Kabuyutan. Dengan demikian, beberapa tahapan umum pengembangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: a) Tahap I ketika kompleks Kabuyutan ini dipergunakan sepenuhnya sebagai kediaman Ki Buyut Trusmi sebagai cikal bakal sekaligus pemuka masyarakat Trusmi. Sangat mungkin pada tahap ini Kabuyutan memiliki beberapa kelengkapan sebagaimana pusat pemerintahan di Jawa b) Tahap II ketika kompleks Kabuyutan menyandang peran ganda sepeninggal Ki Buyut Trusmi yakni menjadi tempat pemakaman Ki Buyut sekaligus sebagai tempat kediaman pemukan masyarakat Trusmi yang menggantikan Ki Buyut 163 c) Tahap III ketika kompleks Kabuyutan menjadi Kramat atau situs yang dimuliakan yang sepenuhnya berfungsi sebagai tempat peziarahan dan peribadatan. Tak ada lagi fungsi sebagai kediaman maupun pemerintahan di sini. Elemen-elemen yang diyakini oleh masyarakat setempat telah ada di masa hidup Ki Buyut Trusmi adalah: a) Witana yang disebut sebagai bangunan yang pertama kali dibuat. Masyarakat setempat memercayai bangunan ini semula berfungsi sebagai tempat Ki Buyut menerima tamu atau memimpin pertemuan. Mengingat statusnya sebagai bangunan asal mula maka cukup beralasan kalau bentuk, dimensi dan lokasi bangunan ini tidak berubah meskipun semua komponennya pernah diganti beberapa kali. b) Kediaman Ki Buyut Trusmi yang kemudan menjadi tempat penguburannya. Mengingat kedudukan kuburan bersifat permanen maka sangat mungkin lokasi bangunan ini tidak pernah berubah meskipun bentuk dan dimensi bangunan mengalami perubahan. c) Masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Mengingat masjid lazim dijumpai di berbagai pusat pemerintahan maka dapat dipahami jika Masjid di Kramat Buyut Trusmi telah ada sejak awal. Bangunan ini mungkin jauh lebih kecil ketimbang Masjid yang ada sekarang yang baru diperluas terakhir pada pertengahan tahun 1960-an. Dimungkinkan juga bangunan masjid ini pernah bergeser untuk menyesuaikan dengan perkembangan bangunan lain. Ketiga bangunan itu masih menunjukkan jejak sebagai bangunan yang ada sejak semula sehingg ketiganya dibangun dengan atap sirap sementara bangunanbangunan lain menggunakan atap alang-alang. Lebih lanjut, Adimuryanto (2001) yang mendapat keterangan dari almarhum Kiai Ahmad menerangkan bahwa semula Alun-alun Trusmi berada di selatan Witana. 164 Jika keterangan ini dapat dibenarkan maka susunan bangunan-bangunan inti pada kompleks ini dapat dipahami menyerupai susunan pusat pemerintahan di Jawa. Ketika bangunan kediaman Ki Buyut Trusmi berubah menjadi makam, maka didirikanlah bangunan lain yang berfungsi sebagai kediaman pemuka kawasan Trusmi dan tempat dia memimpin masyarakat. Di antara bangunan yang ada yang paling menyerupai tempat kediaman adalah kluster yang terdiri atas Paseban, Bale Kiai dan Bale Kunci. Kluster ini memiliki elemen dan susunan yang menyerupai Omah Gede dan Bale Gede yang memang dibangun sebagai kediaman seorang pemuka. Omah Gede dan Bale Gede terdiri atas dua bagian yang memiliki bentuk serupa namun pelingkup yang berbeda. Di depan terdapat Bale yang terbuka dan Omah di belakang yang tertutup. Paseban di depan berupa bangunan terbuka tak berdinding sedangkan Bale Kunci dan Bale Kiai memiliki pelingkup yang rapat. Di utara kluster ketiga bangunan tersebut namun dibatasi dengan pagar pasangan bata terdapat bangunan dapur yang cukup besar. Keberadaan dapur ini memperkuat dugaan bahwa bagian ini semula memang dibuat sebagai lingkungan domestik atau tempat kediaman. Namun demikian terdapat perbedaan orientasi dan konstruksi yang membedakan kluster bangunan ini dengan Omah Gede. Sebagaimana kebanyakan rumah Jawa, Omah Gede dan Bale Gede memiliki orientasi ke arah selatan sedangkan kluster Paseban di Kramat berorientasi ke barat. Bangunan terbuka di Bale Gede dan Omah Gede memiliki konstruksi pengikat kolom di bawah sehingga membentuk amben di antara keempat kolom tersebut sedangkan di Kramat justru bangunan tertutup yang terletak di belakang yang memiliki konstruksi seperti itu. 165 KLUSTER AWAL KLUSTER PENGEMB ANGAN Gambar 4.34. Dugaan pengembangan awal Kramat Buyut Trusmi Secara fisik, kluster kediaman ini dapat dibedakan dengan jelas dengan tiga bangunan awal karena semua bangunan di atap ini beratap alang-alang sehingga berbeda dengan pendahulunya yang beratap sirap kayu. Meskipun dari luar tampak lebih bersahaja dibandingkan bangunan beratap sirap, namun dari dalam bangunanbangunan ini menunjukkan kecanggihan tertentu. Bangunan Paseban memiliki bentang struktur utama yang paling lebar di antara bangunan-bangunan di seluruh kompleks. Di atas blandar panjang yang menghubungkan saka gurunya terdapat tumpukan balok seperti tumpang sari di Jawa. Konstruksi ini memiliki artikulasi yang kuat dengan ornamen ukiran yang rumit pada ganja dan susunan balok-balok tersebut. Kluster ini berada di bagian barat sedangkan kluster tiga bangunan awal berada di timur. Ruang terbuka yang membujur timur-barat dengan gapura di kedua ujungnya di Kramat Buyut Trusmi tampaknya adalah jalur utama yang menghubungkan kedu kluster yang dibangun pada tahapan yang berbeda ini. Kemungkinan jalur akses dari arah barat yang memiliki serangkaian gerbang 166 berbentuk candi bentar juga terbentuk pada tahap yang sama dengan kluster baru tersebut. Lama-kelamaan peran politis pusat kawasan Trusmi ini menyurut sedangkan peran spiritualnya sebagai tempat peziarahan berkembang sehingga keseluruhan kompleks ini menjadi Kramat yang menyandang peran sebagai pusat spiritual sebagaimana yang dijumpai saat ini. Pemuka Trusmi tampaknya tak lagi berkediaman di kompleks Kramat. Kemungkinan berada di Omah Gede yang hingga sekarang masih menyandang status sebagai bangunan terpenting di Trusmi di luar Kramat. 4.8.2. Perkembangan Lanjut (1926 hingga sekarang) Perkembangan lebih lanjut di akhir masa kolonial hingga saat ini menunjukkan dinamika yang penting. Peta Kramat Buyut Trusmi yang dipublikasikan bertarikh 5 April 1926 (Muhaimin, 2006). Dalam peta yang berjudul Pekoeboeran en Pekarangan Roemah Djimat Ki Gedeng Trusmi tersebut Kramat Buyut Trusmi beserta lingkungan sekitarnya berada di bawah kewenangan Kraton Kasepuhan Cirebon. Dalam keterangan peta tersebut dijelaskan bahwa batas tanah merujuk pada patok yang ditetapkan pada tahun 1898. Trusmi sebagai entitas politik telah sangat tereduksi sehingga kehadiran entitas ini dalam peta tersebut tinggal diwakili oleh bangunan balai desa kecil di sudut barat daya. Reputasi kawasan ini bertahan karena keberadaan “Roemah Djimat” atau Kramat. Kramat Buyut Trusmi, dalam peta tersebut, diposisikan di tengah dengan dikelilingi oleh pemakaman di sisi selatan, utara, dan timur termasuk yang sekarang menjadi tanah lapang yang biasa disebut sebagai Alun-alun Trusmi. Sisi barat digambarkan sebagai permukiman padat yang sekarang dikenal sebagai Blok Jero dengan bangunan pusaka Omah Gede di tengahnya. 167 Gambar 4.35. Peta Permukiman dan Kramat Buyut Trusmi tahun 1926 (dalam Muhaimin 2006) Elemen bangunan dan ruang terbuka serta susunannya serupa dengan yang dapat kita jumpai di Kramat saat ini. Bagian timur didominasi oleh bangunan Makam dan Witana yang terletak segaris dengan dua gapura berurutan di antara kedua 168 bangunan utama tersebut. Bangunan terbesar di sisi barat adalah Masjid dengan kluster Paseban di sebelah utaranya. Penggambaran kawasan sebagai “Permoekiman en Pekarangan” serta Kramat sebagai kompleks makam dan kompleks penunjangnya menunjukkan karakter berganda dari Kramat Buyut Trusmi dan lingungan sekitarnya. Dalam peta tersebut baik Kramat maupun kawasan Trusmi terdiri atas dua bagian yang berupa lingkungan pemakaman di timur dan lingkungan hunian di barat. Beberapa objek yang memiliki nilai kesakralan diberikan keterangan secara khusus yakni Batu Pendadaran, Balong Pakulahan dan Sumur Jimat yang terletak di antara Sungai Glagah dan dinding Kramat. Semua objek ini terletak di sisi timur yang memang memiliki karakter sakral. Dengan membandingkan antara rinci peta tersebut dengan kondisi sekarang kita dapat memiliki gambaran bahwa pola ruang dan bangunan di Kramat Buyut Trusmi sudah cukup mapan. Namun demikian, hal ini tidak berarti perubahan pada bangunan telah usai. Tak lama setelah tarikh peta tersebut dimulailah sejumlah pembangunan di Kramat yang penting. Masyarakat Trusmi tampaknya menyadari momen-momen perubahan ini sehingga mereka menorehkan angka tahun di banyak bagian bangunan untuk menunjukkan saat terjadinya perubahan. Semua bangunan tersebut ditengarai dengan tarikh Masehi, beberapa diantaranya dilengkapi juga dengan tarikh Hijriyah. Secara kronologis bangunan-bangunan yang memiliki tanda tersebut adalah: • Gapura Dalam Makam (1931) • Gapura Luar Makam (1957) • Gapura Timur (1958) • Gapura Barat (1958 dan 1965) • Pintu ke Ruang Utama Masjid (1969) • Pintu ke Ruang Samping Masjid dari serambi (1989) 169 Gambar 4.36. Angka tahun yang tertera pada berbagai bangunan Dapat ditengarai di situ bahwa penandaan pembangunan dijumpai pada dua kelompok bangunan yakni bangunan gapura dan bangunan masjid. Semua gapura di Kramat Buyut Trusmi kecuali gapura menuju ke dapur ditandai dengan angka tahun akan tetapi tidak dijelaskan apa yang dilakukan terhadap gapura-gapura tersebut di tahun-tahun yang tercantum kecuali gapura barat yang menghadap ke Paseban dan gapura timur (lawang wetan). Pada plakat kayu yang terpasang di ambang atas pintu barat terbaca tulisan: “Pintu sebelah barat dipasang sirap pada tanggal 10-7-1958 Kamis 22 Rajaagung Wawo”. Sedangkan pada posisi yang sama di pintu timur terbaca “Bangunan lawang wetan 18-5-1958 27 Sebtupaing Sawal Wawo”. Pada gapura barat jelas terbaca bahwa yang dilakukan pada saat itu adalah pemasangan sirap. Kiai Warlan memberikan penjelasan bahwa semula gapura-gapura tersebut beratap welit namun pada akhir daswarsa 1950-an semua diganti neratap sirap. 170 Karena kedekatan waktunya maka sangat mungkin bahwa gapura timur Kramat dan gapura luar Makam menjalani proses yang sama. Gambar 4.37. Angka tahun di konsol gapura dalam makam Pada tahun 1965 gapura barat diganti dengan bangunan baru yang sarat dengan ukiran simbolis; sedangkan bangunan pintu barat yang lama dipindahkan ke timur untuk menggantikan gapura timur yang lebih sederhana dan telah lapuk. Saat penggantian pintu barat ini juga terjadi pada tahun Wawu, dengan demikian tepat satu windu setelah penggantian welit menjadi sirap di pintu ini. Mengingat Buka Sirap hanya dilaksanakan pada tahun Alip dan Dal maka pembaruan pintu pada tahun 1958 dan 1965 adalah pekerjaan khusus yang tidak dikaitkan dengan prosesi Buka Sirap. Dengan demikian terdapat dua jenis peristiwa yang terjadi pada bangunan gapura ini. Yang pertama adalah pembaruan parsial. Bukan hanya penggantian atap welit yang dilakukan secara berkala saat Memayu, pada tahun 1958 atap gapura ini diperbarui dengan material yang berbeda dari atap welit menjadi atap sirap sehingga perlu ditandai dengan plakat tersebut. Peristiwa kedua adalah pembangunan baru secara keseluruhan gapura barat yang diikuti dengan pemindahan gapura lama ke timur. Inskripsi untuk memeringati pembangunan baru gapura barat ini adalah yang 171 memuat informasi terlengkap bukan hanya tarikh Hijriyah dan Masehi secara rinci tapi juga memuat keseluruhan nama ketiga belas pengelola makam dan bahkan para tukang yang mengerjakan gapura tersebut. Namun demikian tidak ada penjelasan tentang tindakan yang dilakukan pada gapura ini. Tidak terdapat informasi yang memadai tentang apa yang terjadi pada tahun 1931 dan 1957. Mengingat kedekatan tahun 1957 dengan tahun 1958 saat gapura barat diganti menjadi beratap sirap maka kemungkinan gapura luar Kabuyutan menjalani proses yang sama. Jika tahun-tahun yang tercantum pada gapura tersebut diurutkan, maka tahun yang paling tua ditemui di gapura dalam menuju Makam Kabuyutan (1931) yang diikuti dengan gapura luar (1957) dan yang terakhir gapura barat (1958 dan 1965). Jalur rangkaian gapura tersebut adalah jalur utama menuju ke Kabuyutan yang dilalui oleh seorang peziarah. Dapat dipahami bahwa transformasi ini adalah wujud monumentalisasi jalur prosesi peziarahan yang menekankan status Kabuyutan Trusmi sebagai Kramat atau Roemah Djimat tersebut. Dalam proses monumentalisasi ini artikulasi simbolis pada gapura barat yang diukir dengan lambang-lambang yang menerjemahkan narasi asal muasal Trusmi dan tokoh cikal bakalnya dapat dipahami sebagai upaya komprehensif untuk klaim supremasi dan senioritas Trusmi terhadap Kramat lain yang bertebaran di seluruh Cirebon khususnya terhadap Astana Gunungjati. Pembaruan besar-besaran yang kedua adalah yang terjadi pada pertengahan dasawarsa 1960an terhadap bangunan Masjid. Kiai Warlan mengingat bahwa pembaruan Masjid yang memerlukan dana sangat besar itu dimungkinkan karena sumbangan dari para juragan batik di Trusmi. Kiai Warlan menyebutkan bahwa gagasan besarnya datang dari almarhum Kiai Ahmad. Masjid yang ada pada saat itu memiliki luasan lantai yang relatif kecil dan atap yang rendah. Kiai Ahmad ingin meninggikan dan memperluas Masjid tersebut. Empat kolom utama Masjid yang semula berpenampang silinder dengan ketinggian kurang dari 3 meter diganti dengan kolom persegi setinggi sekitar 4 meter. 172 Kolom-kolom serambi yang berpenampang persegi disambung dengan balok persegi dan kemudian diperkuat dengan papan kayu yang membungkus sambungan hingga lantai di keempat sisinya. Beberapa tiang silindris tersebut kemudian dipindahkan ke pendopo di depan gapura dalam Kabuyutan. Setelah tahun 1969, Masjid tersebut tak lagi mengalami pembangunan besar. Beberapa perubahan kecil namun dapat memberikan gambaran tentang pemahaman terhadap material dan pembangunan terjadi sesudahnya. Pada pertengahan dasawarsa 1970-an pohon belimbing di utara Masjid roboh tang mengakibatkan kerusakan atap Masjid yang cukup parah. Mustaka Masjid yang terbuat dari gerabah pecah. Pengelola Kramat mengganti hiasan puncak tersebut dengan mustaka yang terbuat dari logam, setelah menyimpan mustaka lama di Bale Pasalinan. Pada saat arakarakan jelang Memayu, mustaka yang pecah tersebut diarak dan terjadi peristiwa gaib yang menyebabkan kematian seorang penonton di dekat mustaka yang sedang diarak tersebut. Peristiwa ini dipahami sebagai isyarat bahwa semestinya mustaka Masjid tetap terbuat dari tanah liat, bukan logam. Secara tradisional mustaka gerabah haruslah dibeli di Desa Panjunan karena desa ini di zaman awal berdirinya Cirebon adalah tempat pembuatan gerabah khususnya yang berupa wadah air atau “jun” sehingga disebut Panjunan. Akan tetapi, pada saat ini tak ada lagi pembuat gerabah di desa tersebut. Untuk memenuhi syarat tradisi, seorang pembuat gerabah dari Desa Jamblang dipesan untuk membuat mustaka. Sesudahnya, dia didatangkan ke Panjunan untuk melakukan transaksi penjualan mustaka tersebut. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa lokasi geografis asal material atau komponen bangunan dalam hal tertentu menentukan kecocokan komponen yang akan dipasang tersebut. Pada tahun 2010 terjadi penggantian komponen yang penting di Masjid. Pintu utara yang langsung menuju ke shaf terdepan, yang biasa disebut Pintu Kiai karena memang dikhususkan untuk para Kiai memasuki Masjid memerlukan penggantian karena telah usang. Pintu lama yang masih relatif bagus kemudian dipasang di Jinem Wadon yang terletak di barat Masjid. Beberapa waktu kemudian 173 terjadi gunjingan di antara warga yang merasa bahwa komponen Masjid yang telah usan tak semestinya dipasang di luar Masjid. Akhirnya dengan desakan warga, pintu tersebut dipindahkan dari Jinem Wadon untuk mengganti pintu yang menghubungkan ruang shalat Masjid dan ruang shalat perempuan di sisi selatan Masjid. Meskipun pemindahan sirap bekas dari Masjid ke bangunan lain setiap saat terjadi, namun komponen tertentu yang dianggap penting tak semestinya dipindahkan keluar Masjid sebagaimana diungkapkan dalam peristiwa ini. 4.9. Beberapa Temuan Dari paparan di atas dapat dipahami beberapa pola pembuatan lingkungan binaan atau arsitektur dalam arti yang luas dengan melibatkan kepanggahan dan ketidak-panggahan. Dalam perkembangan dan pembangunan kembali secara berkala di Kramat Buyut Trusmi bangunan-bangunan diperbarui dengan material baru maupun material pindahan dari bangunan lain dengan tetap mempertahankan bentuknya. Dalam hal ini bentuk menjadi bersifat panggah sedangkan material bersifat tak panggah. Beberapa prinsip penting tentang ketidak-panggahan material dapat didalami lebih lanjut, antara lain: a) Kebaruan material sebagai ungkapan keunggulan bangunan Kebaruan Bangunan Makam Ki Buyut yang selalu menggunakan material baru menunjukkan kesakralannya justru dengan ketidak-panggahan bendawinya. Kebaruan tidak dipandang bernilai rendah karena bangunan tersebut dipandang memiliki bentuk dan kedudukan yang asali. Kabuyutan dalam hal ini didudukkan dalam posisi tertinggi karena dianggap mampu menarik kontributor untuk memberikan material baru tapi juga sekaligus mampu selalu memberikan material “layak pakai” untuk diterapkan pada bangunan lain di Kramat. b) Kebaruan bangunan dipandang sebagai kekurangan Hal ini berbeda dengan bangunan Bale Keprinci, Jinem Wadon dan Pawadonan yang dipandang sebagai bangunan baru sehingga belum semestinya diperbarui dengan teknik sebagaimana pada bangunan yang lama. Welit di ketiga 174 bangunan tersebut tetap dipasang tanpa rangken untuk membedakan dengan bangunan yang sudah mapan. Hal yang sama terjadi pada Pendopo Makam dan Penutup Sumur Jimat yang tidak selalu diperbarui lantaran dipandang sebagai bangunan tambahan. Gambar 4.38. Gapura dalam Makam yang diubah penutup atapnya dari welit menjadi sirap c) Pengubahan material untuk peningkatan status Keempat gapura di Kramat yang semula beratap welit diubah menjadi beratap sirap. Pengubahan ini memerlukan pentahbisan khusus sebagaimana terbaca dalam plakat yang terpampang pada bangunan-bangunan tersebut. Tampaknya penggantian ini juga diperhitungkan berdasar pola waktu tertentu mengingat tahuntahun yang tercantum adalah tahun Wawu yang merupakan tahun antara dua Buka Sirap di tahun Dal dan Alip. d) Ketidak-panggahan dan nilai spiritual Ketika suatu komponen bangunan dilepaskan dari bangunan asalnya yang bersifat sakral maka komponen tersebut dapat mempertahankan nilai kesakralannya atau kehilangan. Komponen yang unik dan dapat diidentifikasikan dengan mudah sebagai bagian dari bangunan asal dipandang memiliki nilai yang tinggi seperti bekas 175 mustaka Masjid yang disimpan di Bale Pasalinan dan bekas nisan kayu Ki Buyut yang dikubur di samping Kabuyutan. e) Ketidak-panggahan dan nilai sosial Upaya pembangunan kembali secara terus menerus adalah suatu praktik sosial yang melibatkan banyak orang. Saat peristiwa tersebut berlangsung nilai-nilai sosial sebagaimana terwujud dalam praktik direproduksi. Buka Sirap lebih menekankan pada nilai sosial yang bersifat hirarkis dengan tatacara yang cermat yang dikaitkan dengan kelompok yang memiliki hak-hak khusus dalam pembangunan sementara yang lain menjadi pendukung. Memayu lebih berorientasi pada nilai yang egaliter sehingga pada dasarnya setiap orang dapat beraprtisipasi secara setara. Jika Memayu dan Buka Sirap dipahami sebagai ritual maka keduanya adalah ritual yang menekankan pada kebersamaan dengan memosisikan setiap orang sebagai pelaku. Tidak ada penonton dalam ritual ini karena setiap orang berupaya untuk menjadi partisipan. Semua orang adalah pembuat bangunan sekaligus pengguna bangunan. f) Ketidak-panggahan sebagai pelestarian pertukaran Dalam jejaring komunal dengan nilai spiritual yang kuat seperti di Trusmi, Kramat dipandang sebagai mata air berkah yang bisa didapatkan oleh mereka yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Kesungguhan itu dibuktikan dengan kontribusi harta, benda dan tenaga yang dipersembahkan di setiap kesempatan tapi memiliki skala yang luar biasa pada saat prosesi besar seperti Memayu dan Buka Sirap. Event tersebut senantiasa diperlukan agar sekerap mungkin dan sebanyak mungkin orang dapat berkontribusi. Pemilihan material dan teknik tak panggah adalah untuk melestarikan kesempatan meperbarui tersebut, yang berarti kesempatan untuk mendapat berkah melalui pertukaran. 176 BAB 5 MENAFSIR MAKNA MENJADI KONSEP-KONSEP DASAR Cara orang-orang Trusmi berarsitektur yang khas di Kramat Buyut Trusmi, suatu tempat yang mereka anggap sentral dalam berkehidupan, telah disajikan pada Bab 4. Pemaparan mendalam ini meliputi wujud bangunan, susunan ruang, teknik membangun, peran dan hubungan antar pelaku pembangunan serta tata cara melakukan ritual. Lebih dari sekedar penyajian fakta empiris pada tempat dan peristiwa tertentu, paparan mendalam ini memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang hal-hal mendasar yang melandasi fenomena praktik arsitektur di Kramat Trusmi. Untuk dapat menafsirkan paparan fenomena tersebut menjadi suatu konsep yang terstruktur dan asasi diperlukan serangkaian proses iteratif yang digambarkan oleh Geertz (1982: 17) sebagai berikut: Suatu lingkaran hermeneutika terbentuk oleh relasi dialektik antara bagian dan keseluruhan. Bagian-bagian tersusun membentuk keseluruhan, sedangkan keseluruhan memberi makna bagi tiap bagian. Ada dua hal yang harus dipertemukan untuk menafsir suatu budaya dalam lingkaran hermenutika ini: paparan tentang suatu wujud simbolis (gerak ritual atau patung pemujaan) sebagai ekspresi yang terdefiniskan; dan kontekstualisasi wujud tersebut ke dalam suatu struktur makna yang terbentuk oleh jejaring wujud-wujud simbolis tersebut yang sekaligus menjadi sesumber penafsiran makna. Untuk dapat menafsirkan suatu keseluruhan dengan baik, pertama-tama kita perlu untuk mengenali komponen-komponen dari totalitas tersebut dan kemudian 177 menggabungkannya sehingga menjadi keutuhan yang bermakna. Langkah ini terjadi terus menerus. Dalam konfirmasi ini triangulasi terjadi. Luaran dari proses dialektis ini adalah sejumlah konsep yang meliputi: tempat, waktu, material dan membangun. 5.1. Konsep Tempat Berbatas tembok pasangan bata yang dicat merah setinggi dua meter, kompleks Kramat Buyut Trusmi terlihat sebagai tempat khusus yang dibedakan dari lingkungan di sekitarnya. Gapura dengan bukaan rendah yang mengharuskan kita membungkuk, gentong air di kiri kanan pintu gapura tersebut yang mempersilahkan kita bersuci, serta dinding penyekat kuta hijab di balik pintu yang menghalangi pandangan kita, secara bersama-sama mengungkapkan pesan tentang penghormatan, penyucian dan pengendalian diri ketika kita memasukkan salah satu dari kedua gapura menuju ke Kramat. 5.1.1. Tempat Cikal Bakal Pertama-tama Kompleks Kramat Buyut Trusmi diyakini sebagai bangunan cikal bakal di wilayah tersebut. Salah satu versi menyebutkan bahwa Ki Gede Alangalang sebelumnya bertapa di tempat ini ketika masih berupa padang ilalang, tetapi Ki Buyut Trusmilah yang menjadikan tempat ini sebagai kediaman. Sejarah atau lebih tepat memori tentang Trusmi sangat terfragmentasi. Berhenti pada generasi pertama tanpa ada narasi kronologis yang menuturkan perkembangan berikutnya mengingat Ki Buyut tidak meninggalkan keturunan dan pemuka penggantinya juga sangat sedikit diceritakan. Dalam konteks sejarah yang terpenggal ini, kompleks Kramat Buyut Trusmi menyandang peran penting untuk mempersatukan masyarakat yang sekarang berkediaman di sekitar Kramat maupun yang ada di luar kota; serta menjalin hubungan antara masyarakat sekarang dengan asal muasal mereka di masa silam yang jauh. Tak ada silsilah, kekerabatan maupun riwayat suksesi kepemimpinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak seperti bangunan bersejarah yang 178 mengandalkan nilai pentingnya dengan mengaitkan diri terhadap narasi kronologis. Di Trusmi, Kompleks Kramat adalah sejarah itu sendiri. Orang berafiliasi dengan Kramat Buyut Trusmi pertama-tama bukan karena keturunan tapi karena kedekatan atau afinitas mereka dengan Kramat. Kedekatan seseorang dengan Kramat Buyut Trusmi dapat terjalin melalui beberapa cara. Kedekatan yang paling jelas bersifat geografis dengan tempat kediaman seseorang yang berjarak cukup dekat dengan Kramat. Seseorang yang tinggal di Blok Jero dalam hal ini adalah yang dianggap paling dekat. Mereka yang berkediaman di bagian lain dari Desa Trusmi yakni Blok Bangbangan, Klentikan, Kebon Asem dan Sibunder berada pada lingkaran berikutnya. Sementara, di lingkaran berikutnya adalah mereka yang tinggal di luar Trusmi, yakni di desa-desa sekitar yang diyakini memiliki hubungan dengan awal Desa Trusmi, seperti Desa Gamel, Wotgali dan Talitengah. Peran Kramat Buyut Trusmi sebagai cikal bakal permukiman di sekitarnya terungkap dengan jelas pada keberadaan lima rumah kuna yang berafiliasi dengan Kramat. Bangunan yang paling utama dari kelima rumah itu adalah Omah Gede yang terletak Blok Jero, beberapa puluh meter di barat kompleks Kramat. Rumah ini diyakini sebagai rumah pertama yang dibangun di luar Kramat untuk murid Ki Buyut yang paling menonjol. Beberapa orang menyebutnya sebagai Ki Gede Trusmi. Keempat rumah yang lain disebut sebagai Bale Gede yang berada di berbagai penjuru. Bangunan-bangunan tersebut saat ini dimiliki oleh Pak Baskar, Pak Sukandi, Pak Kadima dan Kiai Warlan. Nama-nama pemiliki tersebut dipergunakan untuk menyebut bangunan-bangunan kuna ini lantaran masyarakat dan pemiliknya tak lagi mengetahui siapa nama pembangunnya. Selain karena tempat kediaman, kedekatan juga terbentuk karena intensitas hubungan seseorang dengan Kramat Buyut Trusmi. Sep adalah orang yang secara formal menduduki posisi tertinggi dalam hal kedekatan karena intensitas hubungan ini. Mengingat jabatan ini tidak didasarkan pada garis keturunan atau kemampuan spiritual tertentu tetapi berdasarkan pilihan warga, Sep menduduki jabatan sebagai 179 konsekuensi dari kedekatannya dengan masyarakat yang secara geografis tinggal di sekitar Kramat. Sesudah terpilih, seorang Sep baru kemudian memiliki intensitas hubungan yang sangat tinggi dengan Kramat. Sesudah Sep adalah posisi yang diduduki oleh para Kiai, Kunci, Kemit dan Kaum. Kecuali jabatan Kemit yang didasarkan pada penunjukan, semua jabatan tersebut didasarkan pada pilihan oleh warga sehingga memiliki relasi sosial-spasial sebagaimana jabatan Sep. Masingmasing dari mereka memiliki peran khusus yang bersifat internal sedangkan Sep mewakili semua pengelola Kramat sekaligus menjalin hubungan ke luar. Para peziarah memiliki intensitas hubungan yang kuat namun bersifat sesaat. Saat masuk ke kompleks Kramat Buyut Trusmi, orang yang akan berziarah atau tirakat melepas alas kaki di pintu sebagai tata krama memasuki Kramat yang dimuliakan. Kemudian merekan menyucikan tubuh dengan mandi di Balong Pekulahan dan Sumur Jimat. Dua gerbang menuju makam diapit dengan gentong air yang disediakan bagi mereka yang akan menyucikan diri lebih lanjut. Kemudian mereka berdhikir dan berdoa di depan makam dengan mengorientasikan tubuh mereka yang telah disucikan ke arah pintu kecil berukir dengan kemenyan yang senantiasa menyala di sampingnya. Serangkaian tatacara ini menegaskan bahwa afinitas dengan Kramat dibangun melalui serangkaian praktik yang memosisikan tubuh di dalam ruang yang ketika dilaksanakan secara terus menerus membangun kesakralan Kramat itu sendiri. Dalam pola pertukaran ini peziarah meyakini mereka beroleh berkah sedangkan Kramat meningkat “ke-kramat-an”nya. Orang tirakat mengawali praktik tirakat mereka sebagaimana peziarah yang kemudian dilanjutkan dengan menginap selama beberapa hari di kompleks Kramat. Dengan demikian tirakat dapat dipahami sebagai ziarah yang lebih intensif. Bagi mereka terdapat serangkaian tata laku yang tidak dijalani oleh para peziarah. Yang paling menonjol dari tata laku ini adalah mereka diharuskan tinggal di Jinem—yang terletak di depan makam untuk laki-laki dan di belakang masjid untuk perempuan— serta menjalankan puasa selama bertirakat. Papan dan praktik mendapatkan penegasannya lebih lanjut di sini. Pemisahan jender lebih ditekankan dalam tirakat 180 ketimbang pembedaan jarak dengan Makam. Seorang tokoh setempat mengisahkan bahwa semula kedua bangunan yang ada di depan Makam itu dipergunakan sebagai Jinem Laki-laki dan Jinem Perempuan. Karena jumlah orang tirakat yang meningkat maka kedua bangunan ini kemudian dipergunakan semua untuk Jinem Laki-laki dan perempuan melakukan tirakat di dekat Masjid. Selama menjalani tirakat, makanan untuk berbuka disiapkan oleh Kemit. Sebagai kelaziman orang yang bertirakat memberikan uang, makanan dan bahan makanan kepada Kemit saat mereka datang dan meminta izin untuk tirakat. Pola hubungan ini dapat dipahami sebagai intensifikasi pertukaran antara kedua belah pihak tersebut. Salah satu Kemit yang saya jumpai berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dia mengawali kedekatannya dengan Kramat ketika melakukan peziarahan yang kemudian diikuti dengan tirakat secara berkala. Dengan peningkatan intensitas hubungan ini, lama kelamaan dia ditunjuk untuk menjadi salah satu Kemit di Kramat Buyut Trusmi. Affinitas spasial dalam hal ini diikuti dengan affinitas sosial. Proses membangun berkala, memegang peran yang krusial dalam membentuk kedekatan dengan penekanan yang berbeda antara Memayu dan Buka Sirap. Memayu adalah peristiwa kewargaan. Seluruh partisipan baik yang berasal dari Desa Trusmi maupun dari desa-desa sekitarnya terlibat dengan cara dan intensitas yang sama. Para pengelola Kramat tak terlibat secara langsung dalam teknis penggantian atap alang-alang tersebut. Sementara, Buka Sirap menekankan pada hirarki yang berbeda membentuk relasi yang berbeda dengan cara dan intensitas dalam membangun. Para tukang yang memiliki keunggulan skill menyiapkan komponen konstruksi namun tidak mendapat kesempatan untuk memasangnya; sedangkan para pemuka Kramat memiliki keterbatasan skill namun menyandang status yang tinggi yang memungkinkan mereka secara absah menaiki bangunan dan mengganti atap sirap khususnya di bangunan Makam. 181 Setiap penyelenggaraan Buka Sirap, para tukang memperbarui relasi. Peta hubungan mereka dengan Kramat dikukuhkan kembali dalam partisipasi panjang selama mempersiapkan sirap secara bergiliran selama dua bulan sebelum pelaksanaan Buka Sirap. Selama sepekan ritual Buka Sirap, mereka mengelola semua komponen bangunan dan menyucikannya sebelum dipasang. Saat kenduri sebagai klimaks ritual mereka mendapatkan berkat besar yang berbeda dengan pengobeng pada umumnya. Pada penyelenggaraan Buka Sirap 2014 terjadi peristiwa tak terduga. Ratusan pemuda dari Blok Jero yang merupakan lingkungan permukiman inti desa Trusmi mengklaim bahwa mereka adalah tukang dan bukan pengobeng meskipun tidak turut mempersiapkan sirap dan hanya aktif saat ritual saja. Kejutan ini dapat teratasi karena persediaan berkat besar cukup banyak untuk dibagikan kepada mereka. Kedekatan keruangan, dalam peristiwa ini diyakini para pemuda dapat meningkatkan kedekatan sosial mereka dengan Kramat sehingga memobilisasi status dari pengobeng menjadi tukang. Dalam kaitaan dengan Memayu dan Buka Sirap, peran Kramat Buyut Trusmi sebagai situs cikal bakal ini bersifat paradoksal. Di satu sisi, kompleks ini haruslah bersifat panggah dari segi lokasi dengan bertahan di tempat yang sama sejak mula berdirinya. Lantaran kepanggahan tersebut, Kramat Trusmi dapat mempertahankan statusnya sebagai tempat asal muasal. Di sisi lain, Kramat Trusmi dapat bertahan untuk membangun relasi yang bermakna dengan masyarakat dengan terus menerus dibangun ulang secara berkala. Ketidak-panggahan material ini mengintensifkan hubungan antara Kramat dan masyarakat sehingga afiliasi mereka dengan Kramat dapat dilestarikan. Kepanggahan papan sekaligus ketidak-panggahan material ini terlihat paling kentara pada bangunan Witana. Sebagai tempat asal muasal yang dipahami sebagai “wiwitane ana” atau yang pertama kali ada, Witana tak berubah tempat, bentuk dan ukurannya. Bangsal kecil ini tidak mewadahi kegiatan yang mengharuskan jumlah orang tertentu harus diakomodasi sehingga dia tidak memerlukan perubahan dimensi sebagaimana Masjid. Fungsi terpentingnya 182 adalah sebagai tempat untuk mengumumkan jadwal Memayu dan Buka Sirap setiap awal tahun penanggalan Hijriyah yang mempertegas karakteristiknya sebagai tempat untuk mengawali hal yang penting. Namun demikian, secara bendawi Witana menunjukkan ketidakpanggahan yang mencolok. Tiang-tiang tepi penyangga bangunan ini menggunakan bekas tiang utama atau saka guru dari bangunan lain. Hal ini terlihat pada bekas lubang purus untuk sunduk yang biasanya hanya dijumpai pada saka guru. Secara teknis relatif mudah untuk menutup lubang tersebut dengan potongan kayu, tapi ternyata lubang-lubang tersebut dibiarkan saja. Mempertontonkan ketidak-panggahan komponen bangunan yang dipindahkan ke Witana menunjukkan kompleksitas karakter bangunan ini yang menegaskan kepanggahan papan sekaligus ketidakpanggahan material. 5.1.2. Tempat yang Bertransformasi Kramat Buyut Trusmi dibangun pertama-tama sebagai pusat suatu lingkungan permukiman yang kemudian berkembang membentuk satelit-satelitnya yang berupa permukiman di Desa Trusmi. Riwayat ini menunjukkan bahwa kompleks ini menjalin relasi keruangan yang ekstensif dengan lingkungan sekitarnya. Secara umum keseluruhan kompleks ini berdenah segi empat yang tak sempurna dengan beberapa distorsi. Kondisi ini menengarai bahwa sepanjang waktu pembentukannya ada sejumlah kekuatan penting yang memengaruhi bangun dasarnya. Bentuk segi empat dikaitkan dengan mata angin yang bermatra semesta. Lintasan matahari seturut sumbu timur barat tergabung dengan arah darat dan laut yang membentuk sumbu utara selatan menjadi orientasi utama Kramat Buyut Trusmi. Laut adalah arah bawah sebagaimana aliran sungai yang tepat berada di depan gapura timur Kramat. Sebagian masyarakat setempat meyakini bahwa semula di desa mereka mengalir sungai besar yang terhubung ke laut. Menurut mereka pernah ditemukan beberapa fragmen kayu lambung kapal yang besar di Trusmi. Selain dimaknai sebagai arah bandar, utara juga arah Kraton Kasepuhan Cirebon dan Makam Gunung 183 Jati. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah selatan dipandang sebagai arah hulu tempat desa Trusmi berada. Pemaknaan ini penting mengingat orang Trusmi memercayai bahwa hal ini menunjukkan senioritas dibandingkan dengan Cirebon dan Dinasti Gunung Jati. Setelah Trusmi menjadi makam, arah utara-selatan mendapatkan makna baru dalam lingkup yang lebih sempit. Sesuai dengan tradisi Islam, jenazah dikubur dengan kepala di utara dan kaki di selatan. Untuk menghormati mereka yang dikuburkan, bangunan makam dan kompleks inti makam dibangun dengan pintu dari arah selatan yang berarti dari arah kaki jenazah. Orientasi ini terlihat jelas pada pintu bangunan makam dan gerbang di depannya. Arah timur diasosiasikan dengan matahari terbit yang menjadi lambang kekuatan kosmis. Bangunan Witana yang dipahami sebagai tempat persidangan ketika Kramat Trusmi berperan sebagai pusat kekuasaan terletak di sisi timur. Meskipun bangunan ini tidak menghadap ke timur, keberadaan kolam suci atau balong pakulahan di sisi ini memberikan gambaran urutan penyucian dari timur menuju tempat yang dimuliakan. Arah barat memiliki makna berlipat tiga di Trusmi. Di satu sisi, barat adalah arah matahari terbenam sehingga diasosiasikan dengan arah istirahat dan privat. Bale Kiai dan Kunci tempat para pengelola makam beristirahat terletak di arah ini. Dalam kaitannya dengan tradisi Islam, arah barat dipahami sebagai arah kiblat yang menghubungkan masjid di manapun dengan Ka’abah sebagai pusat spiritual universal. Mengingat masjid adalah bangunan terbesar di kompleks ini, arah barat atau arah kiblat hadir cukup menonjol sebagai sumbu utama bangunan peribadatan yang memanjang ini. Arah barat juga terkait dengan Omah Gede yang dipercaya sebagai rumah pertama yang dibangun di luar kompleks Kramat. Hal ini menunjukkan arah pertama ekspansi permukiman ke sisi ini. Dengan arti penting arah barat ini maka dapat dipahami mengapa gapura barat memiliki artikulasi estetik dan ungkapan simbolis yang paling kompleks. 184 Arah barat-timur memegang peran penting dalam pembentukan kompleks Kramat Buyut Trusmi dan aktivitas yang berkembang di dalamnya. Jalur sirkulasi di sela bangunan dan dinding yang terbentang dari gapura timur dan barat berperan sebagai “tulang punggung” yang merangkaikan ruang dan ritual di kompleks ini. Pemindahan dan penyucian material, pembagian berkat setelah ritual dan ritus penyucian diri para peziarah, semua mengambil tempat sepanjang jalur ini. Hampir semua bangunan dan halaman berpagar pasangan bata di kompleks ini memiliki akses ke jalur ini yang menunjukkan sentralitasnya dalam merangkai ruang dan halaman yang membentuk konfigurasi ruang Kramat. Gapura Timur tampaknya semula memegang peran yang lebih penting lantaran berhubungan langsung dengan ruang terbuka yang disebut sebagai Alun-alun Trusmi serta sungai yang kemungkinan pernah memiliki peran transportasi yang menghubungkan Trusmi dengan kawasan di sekitarnya dan bahkan ke Laut Jawa. Setelah kompleks ini bertransformasi dari tempat publik menjadi tempat peziarahan Gapura Barat menjadi lebih dipentingkan. Seorang seniman setempat yang serba bisa yang dikenal sebagai Dalang Kamima mengukir daun pintu dan ambang Gapura Barat selama dua tahun dan pintu lama dipindah ke timur. 5.2. Konsep Waktu Sebatang jurai terpasang membujur ke tenggara pada bangunan Makam di Kramat Buyut Trusmi. Di salah satu sisinya ditorehkan angka 26-7-2010 yang menunjukkan saat pemasangan batang kayu tersebut pada saat penyelenggaraan Buka Sirap terakhir yang dipimpin oleh Kiai Ahmad sebelum Sep ini wafat pada tahun berikutnya. Di atas balok jurai itu terpasang keping-keping sirap kayu yang selalu diganti dengan sirap baru setiap delapan tahun dan bubungan jurai yang diganti setiap empat tahun. Waktu dipahami di Trusmi dalam jalinan sejumlah konstruksi yang kompleks. Tanggal 26 Juli 2010 yang tertera pada batang itu hanya terjadi sekali dan tak pernah terulang selamanya, sepanjang masa. Suatu ketika dalam gerak waktu 185 yang progresif secara absolut peristiwa penggantian komponen struktur tersebut terjadi. Sementara itu, Buka Sirap berulang-ulang terjadi. Tindakan yang sama dalam melepas sirap dan bubungan jurai untuk menggantinya dengan komponen baru terus menerus dilaksanakan, tanpa ada kisah sejak kapan tradisi ini dimulai dan tanpa ada rencana kapan akan diakhiri. Di masa kini, ketika semua kalender dan jam telah disinkronisasikan secara global, waktu acapkali dipahami sesuatu yang abstrak, asali, netral, progresif dan universal sehingga dipahami sebagai bergerak maju bersama di manapun juga. Namun demikan, alam mengungkapkan dimensi waktu dengan caranya yang berulang. Dari pagi di suatu hari ke pagi di hari berikutnya terasa memiliki sifat berulang yang kentara ketimbang sebagai bergerak maju yang menjadikan pagi di hari Rabu sama sekali berbeda dengan pagi di hari Kamis. Begitu pula perbedaan dan perulangan antara musim penghujan tahun ini dan musim hujan tahun berikutnya. Sementara ruang yang abstrak dan universal mendapat alternatifnya dengan memandang suatu kedudukan sebagai tempat yang konkret dan bersifat lokal, waktu tidak memiliki cara pandang alternatif yang setara. Keragaman pemahaman tentang waktu baru terasa ketika kita mengaitkannya dengan peristiwa dan benda. Untuk dapat menyatakan suatu peristiwa telah, sedang, bersamaan atau berulang terjadi kita perlu mendudukkan peristiwa tersebut dalam pemahaman tentang waktu yang tak lagi netral. Begitu pula dalam kaitannya dengan suatu benda atau objek. Untuk menyatakannya telah selesai dibuat, sedang dipergunakan atau sedang diperbaiki, diperlukan kerangka waktu yang lebih konkret yang bukan sekedar menyebut tanggal dan jam. Pemahaman tentang waktu adalah hal yang sangat mendasar untuk dapat memahami fenomena arsitektural yang terjadi di Trusmi khususnya yang berkaitan dengan ketidak-panggahan. Secara umum, ketidak-panggahan adalah fungsi waktu yang diterapkan pada arsitektur. Tahapan berikutnya adalah menggunakan bangunan sempurna tersebut sembari berupaya mempertahan agar bangunan tetap dalam kondisi sebagaimana di akhir pembuatannya hingga masa-masa berikutnya. Di 186 Kramat Buyut Trusmi membuat bangunan adalah penggabungan antara peristiwa berulang dan tak berulang yang terjadi dalam kerangka waktu yang berbeda. 5.2.1. Waktu Alam Saat penyelengaraan Buka Sirap usai, bangunan-bangunan beratap sirap di Kramat Buyut Trusmi tampil unik. Dua sisi beratap sirap baru yang berwarna kuning muda sedangkan dua sisi yang lain berwarna hitam kehijauan karena lumut dan kerak yang melapisi permukaannya. Jejak lintasan waktu tersaji begitu kentara pada bangunan-bangunan ini. Kedua bidang atap ini ditutup oleh sirap dengan usia yang berselang empat tahun. Sejak Buka Sirap tak lagi diselenggarakan secara menyeluruh dalam siklus delapan tahunan maka penampilan seperti akan kerap dijumpai di Trusmi. Ketika keseluruhan atap sirap diganti secara bersamaan maka tak ada perbedaan karakter permukaan antara sirap baru dan lama. Di tahun Alip semua sirap diganti dan berangasur angsur sirap-sirap tersebut akan berubah warna menjadi kian tua secara bersama-sama. Penggantian serentak tiap windu ini masih dipraktikkan di Mande Trusmi di Astana Gunung Jati. Bangunan beratap welit tak begitu tampak perbedaannya antara sisi yang baru dan yang telah berumur setahun. Selain siklusnya lebih pendek, permukaan welit juga tak mengundang lumut dan kerak untuk meninggalkan jejak. Perubahan karakter permukaan karena pengaruh cuaca dan organisme yang menyertainya memang tak terhindarkan. Arsitektur dalam banyak tradisi sering berusaha untuk menghapus jejak ini dengan berupaya mempertahankan agar bangunan tetap tampil baru dan cemerlang, tanpa cela dan lapuk-lekang. Orang-orang Trusmi menikmati kedua kondisi ini. Ketika atap masih baru maka mereka terpuaskan akan hasil kerja besar yang usai mereka selenggarakan. Ketika jejak cuaca telah membekas lama maka mereka merasa bahwa karya mereka telah memberi kemanfaatan bagi lingkungan dan penggunanya. 187 Welit yang dan sirap yang telah tak terpakai lagi bisa dibawa pulang oleh para pengobeng. Kiai Tony membanggakan tentang khasiat welit bekas itu. Abu hasil pembakarannya bisa dipergunakan untuk mengatasi berbagai penyakit dan gangguan makhluk gaib. “Semua terpental,” dia menegaskan. Welit bekas dipandang memiliki daya tertentu karena telah menjadi bagian dari lingkungan yang disucikan ini dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, welit seolah “menyerap” pengaruh positif yang ada di lingkungan tersebut yang tetap melekat bahkan saat bidang atap alang-alang ini tak lagi menjadi bagian dari bangunan-bangunan Kramat. Berbeda dengan sirap bekas yang dibawa pulang oleh para pengobeng sebagai sarana mendapatkan berkah dengan disimpan, welit adalah “pusaka habis pakai” karena dipergunakan dengan menaburkan atau mengoleskan abunya. 5.2.2. Waktu Relasional Pemahaman terhadap waktu memegang peran sentral dalam kehidupan dan aktivitas di Kramat Buyut Trusmi. Sebagai suatu Kramat, momen terpenting yang menghidupkan aktivitas di kompleks ini adalah ritual dengan berbagai variasinya, dari yang bersifat individual hingga yang massal. Kalender ritual yang mengatur dinamika kehidupan di Kramat ini didasarkan pada pemahaman tentang waktu bersifat kompleks dan tumpang tindih dari berbagai konstruksi waktu. Tiap malam 1 Muharram atau 1 Sura yang menandai awal tahun Hijriyah atau yang juga disebut sebagai tahun Jawa dilakukan pengumuman saat penyelenggaraan Memayu dan kadang juga Buka Sirap. Sementara ritual-ritual yang lain cukup definitif jadwalnya Memayu dan Buka Sirap tidak pernah ajeg baik dalam kalender Hijriyah maupun Masehi. Kedua upacara besar ini melibatkan perhitungan yang kompleks dengan banyak variabel sehingga penentuannya hanya bisa dilakukan dengan otoritas Sep setelah mempertimbangkan kalender, pergantian musim dan bahkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Ketika saya bertanya tentang bagaimana para pemuka Kramat Trusmi menentukan tanggal penyelenggaraan Memayu dan Buka Sirap pada tahun tertentu, 188 Ki Warlan tidak memberikan jawaban yang jelas namun berusaha menerangkan suatu kerangka waktu dengan membuat matriks di atas kertas. Yang dia lakukan adalah menerangkan sistem perhitungan tradisional untuk menentukan penanggalan Hijriyah yang berbasis pergerakan bulan tanpa harus melakukan observasi terhadap kemunculan bulan pada waktu tertentu karena perhitungan kompleks ini diyakini berulang terus menerus. “Kalender di sini dinamai Abogé, karena diawali pada tahun Alip yang jatuh pada hari Rabu Wagé. Kalau selain di Trusmi mereka menggunakan Asapon yang diawali dari tahun Alip yang jatuh pada hari Selasa Pon”. Dari matriks rumit ini dapat diperhitungkan kapan tanggal 1 Sura atau Muharram tiba dan tanggaltanggal hari raya Islam lainnya. Pertanyaan saya tetap tak terjawab. Baik mengacu pada kalender Masehi atau Tahun Umum maupun Hijriyah, Memayu dan Buka Sirap tidak memiliki tanggal yang tetap. Tiap tahun berubah. Bahkan pada tahun 1435 H terjadi dua kali Memayu. Ki Warlan akhirnya hanya memberikan gambaran tentang pertimbangan penetapan jadwal kedua peristiwa ritualistik tersebut. Memayu pada dasarnya adalah ritus menyongsong musim tanam yang diselenggarakan menjelang awal musim penghujan yang sekaligus juga saat mulai melakukan penanaman padi. Upacara ini, menurutnya, semula diselenggarakan untuk menghimpun kerabat dan warga agar siap menjalani kerja bersama menanam padi. Jika Memayu dilaksanakan terlalu awal atau jauh sebelum hujan datang, masyarakat akan mempertanyakan kemampuan otoritas Kramat untuk memprediksikan saat turunnya hujan. Jika hujan mendahului Memayu maka kepercayaan masyarakat terhadap Sep akan lebih rendah lagi. Sementara pergiliran musim berkaitan dengan peredaran matahari, penetapan jadwal Memayu juga perlu mempertimbangkan kalender Hijriyah yang didasarkan pada peredaran bulan. Upacara tahunan terbesar yang diselenggarakan di Kramat Buyut Trusmi adalah Muludan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Di berbagai tempat, termasuk di Kraton Kasepuhan Cirebon, Muludan dirayakan pada tanggal 12 Rabi’ulawal yang juga disebut sebagai bulan Maulud yang merupakan bulan ketiga. Khusus di Trusmi kelahiran Nabi dirayakan pada tanggal 20 189 Maulud. Mengingat Muludan adalah kenduri terbesar yang melibatkan masyarakat yang sangat luas dengan kontribusi tenaga, dana dan sumber daya lainnya maka jadwal Memayu biasanya dilaksanakan agak jauh sebelum atau setelah Muludan. Pada tahun Alip dan Dal saat penyelenggaraan Buka Sirap, penentuan jadwal Memayu juga mempertimbangkan jarak saat upacara tersebut dari Buka Sirap agar beban sosial dan ekonomi masayarakat dapat didistribusikan dengan lebih merata. Dengan demikian, penetapan jadwal Memayu melibatkan perhitungan perhitungan musim atau di Jawa biasa disebut pranata mangsa, kalender Hijriyah dan dinamika masyarakat. Jadwal pelaksanaan Buka Sirap tampaknya lebih fleksibel. Upacara empat tahunan ini, menurut Ki Warlan semula dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha supaya daging hewan kurban dapat dimanfaatkan untuk kenduri dalam rangka Buka Sirap. Pelaksanaan Buka Sirap dan Memayu juga terkait dengan siklus mingguan. Memayu dilaksanakan pada hari Senin dengan Ider-ideran sehari sebelumnya. Memayu di Omah Gede diselenggarakan pada hari Kamis atau tiga hari setelah acara serupa di Kramat sedangkan di Bale-bale Gede tujuh hari setelah Memayu Kramat. Buka Sirap dimulai pada hari Senin dan diakhiri dengan kenduri pada hari Senin berikutnya. Banyak Kramat dan tempat yang menyandang nilai-nilai spiritual. Masingmasing tempat memiliki kalender upacaranya. Karakteristik dari kalender upacara di Cirebon adalah kemampuan adaptif masing-masing tempat untuk saling menyesuaikan jadwal. Di antara upacara yang paling banyak diselenggarakan adalah peringatan Maulud Nabi Muhammad yang lazim disebut Muludan. Meskipun semua mengakui tradisi bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabi’ul Awal atau bulan ketiga dalam penanggalan Hijriyah yang juga disebut sebagai bulan Maulud atau Mulud dalam logat setempat, namun beberapa tempat di Cirebon memiliki jadwal dan durasi yang berbeda. 190 Muludan Cirebon dimulai dari Keraton Kanoman yang menyelenggarakan pada tanggal 1-8 Mulud yang berbarengan dengan Keraton Kasepuhan yang melaksanakannya pada tanggal 1-12 Mulud. Astana Gunung Jati melaksanakan peringatan pada tanggal 12 Mulud saja sebagaimana Desa Tuk pada tanggal 19 Mulud dan Desa Gegesik pada tanggal 21 Mulud. Kramat Buyut Trusmi menyelenggarakan upacara peringatan Muludan ini yang paling akhir tapi sekaligus paling lama yakni tanggal 12-25 Mulud. Muludan Trusmi adalah yang paling ramai dukunjungi masyarakat, kedua setelah Keraton Kasepuhan. Pedagang dan hiburan berjajar sepanjang jalan di desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Weru Lor dan Kaliwulu. 5.3. Konsep Material Sambil memantau pelaksanaan Memayu tahun 2015, Kiai Tony berbincang dengan saya tentang pentingnya bangunan di Kramat Buyut Trusmi untuk tetap beratap ilalang dan sirap. Menurutnya, bangunan tak selayaknya beratap genteng dari gerabah seperti lazimnya bangunan saat ini karena gerabah berasal dari tanah liat. Meletakkan tanah di atas bangunan akan menjadikan rumah seperti kuburan. Bahkan untuk bangunan Kramat yang jelas merupakan naungan bagi makam Ki Buyut Trusmi pun tak selayaknya beratapkan tanah. Material yang tersedia di alam seperti batu dan tanah, atau yang dibudidayakan seperti ijuk, kayu dan alang-alang menjalani suatu proses sehingga dapat menjadi bagian dari suatu bangunan di Kramat Buyut Trusmi. Namun demikian, membentuk bangunan bukanlah satu-satunya tujuan dari keberadaan suatu material. Berbeda dengan Louis I. Kahn yang dapat mengajukan pertanyaan hakiki terhadap bata tentang apa yang “dikehendaki” untuk diwujudkan oleh sang bata. Di Trusmi material dibentuk, diproses dan dipasang hanyalah satu dari sejumlah keniscayaan perjalanan yang mungkin dijalani oleh sang material tersebut. 191 Bagian ini menjalin konsepsi tentang material melalui pemahaman tentang asal-muasal material, proses yang dialami oleh material serta relasi sosial yang terbentuk selama pemrosesan material tersebut. 5.3.1. Material sebagai Penanda Tempat Kediaman Alih-alih genteng tanah liat, sirap kayu atau alang-alanglah yang pantas untuk menjadi penutup atap agar bangunan tak jadi seperti kuburan. Lebih dari sekedar sarana pemenuhan kebutuhan akan lindungan dan naungan, penerapan material yang tepat—ketimbang jenis material itu sendiri—akan menentukan apakah tempat yang diciptakan menjadi hunian atau kuburan. Material, dalam cara pandang ini, diklasifikasikan menjadi material kebumian seperti tanah liat dan batu alam, serta material organik yang berasal dari tumbuhan seperti rumput alang-alang dan pohon jati. Tanah dapat ditumpuk, dibentuk dan dipadatkan; sedangkan batu lazim dipotong dan disusun. Sebagaimana di tempat asalnya, bumi adalah yang dipijak sehingga sepantasnya berada di bawah. Dengan ditinggikan dan dipadatkan, tanah dibentuk menjadi batur atau ladasan berdirinya bangunan. Masjid yang memiliki batur dengan ketinggian sekitar 45 sentimeter adalah bangunan dengan batur tertinggi di Kramat Buyut Trusmi. Bangunan-bangunan lain termasuk Makam dan Witana hanya memiliki batur berketinggian sekitar 20 sentimeter. Hanya Masjid yang memiliki batur persegi, sedangkan bangunan lain berbatur persegi panjang. Dengan batur ini ruang bangunan yang tak berdinding didefinisikan. Paseban, Bale Keprinci dan Bangsal Peziarahan menegaskan batasnya dengan peninggian lantai ini. Jinem Lanang dan Witana memperkuat peninggian lantai dengan pagar jeruji kayu. Masjid, Jinem Wadon dan Makam Ki Buyut memiliki dinding bata di seputaran lantainya. Di atas batur diletakkan umpak sebagai landasan yang akan mempertemukan tiang dan batur. Hampir semua tiang di Kramat Buyut Trusmi terbuat dari batu dengan bentuk piramida terpancung yang kadang ditambah dengan bentuk balok di 192 bawahnya. Selain itu, hanya beberapa umpak Jinem yang tampaknya terbuat dari pasangan bata merah berpenampang persegi. Tanah dicetak menjadi batu bata yang ditumpuk untuk membentuk tembok pembatas ruang dalam maupun ruang luar atau halaman. Sekeliling Kramat dibatasi oleh pagar tembok tebal setinggi dua meter yang bercat merah tua sehingga menjadi sosok yang sangat kentara di lingkungan tersebut. Tiga pasang gapura bentar yang mengantarkan pengunjung masuk dari jalan besar dan dari kampung menuju gapura barat juga sosok yang sangat jelas terbuat dari pasangan bata. Material kebumian dipahami sebagai pembentuk lingkungan yang panggah. Jajaran 17 Batu Pendadaran di depan Jinem menegaskan tentang kepanggahan kedudukan batu andesit bulat tersebut meskipun tanpa dilepa sehingga diperlukan upaya keras untuk memindahkannya. Bumi digali untuk menghadirkan air sehingga membentuk sumur dan kolam. Air adalah elemen primordial yang penting untuk membentuk kehidupan dan menyucikan diri. Sumur Jimat di utara Masjid dan Balong Pakulahan di timur Witana adalah wujud paling nyata bagi upaya ini. Keduanya adalah sumber air yang dikisahkan tak pernah kering bahkan di saat kemarau terpanjang. Sumur Jimat tak tampak berbeda dibandingkan dengan sumur biasa, hanya di atasnya didirikan bangunan beratap pelana untuk menaunginya. Balong Pakulahan memiliki sosok yang istimewa, kolam dengan mata air didasarnya ini berbentuk persegi dengan undak-undakan di sisi barat yang dibuat dengan memahat tanah dan memperkuat hasil pahatan itu dengan pasangan bata. Undak-undakan ini berperan penting saat penyucian komponen bangunan yang akan dipasang saat Buka Sirap. Para pengobeng berjajar di tiap trap undakan itu untuk secara beranting membawa sirap, papan dan balok dari tempat penyimpanan ke kolam dan dari kolam ke bangunan yang dituju. Dengan menjadi bagian proses penyucian komponen bangunan, air di Balong Pakulahan meresap ke dalam batang dan bilah kayu tersebut. Material bumi menyatu ke dalam material organik di seluruh bangunan. 193 Banyak peziarah melakukan ritual dengan mandi di kedua sumber air ini. Dengan basah kuyup mereka berlarian dari satu sumber ke sumber yang lain. Jalur setapak di utara Masjid menjadi lintasan utama ritual ini. Setelah diambil dari dalam tanah, air ditampung dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Karena posisinya yang tak pernah berpindah, wadah-wadah air itu menjadi bagian dari tempat kedudukannya. Sepasang wadah air dipasang mengapit keempat gerbang di Kramat Buyut Trusmi: gapura barat, gapura timur dan kedua gerbang menuju Makam dari arah Masjid. Memasuki lingkungan Kramat adalah menyucikan diri sehingga sepasang bejana ini mengingatkan akan upaya meraih kesucian ini. Seorang peziarah yang memasuki Makam harus melintasi tiga gerbang yang diapit bejana air ini. Tiga bejana yang terbuat dari tanah liat terdapat di sisi utara Masjid. Satu gentong berpancuran atau padasan diletakkan di sisi timur pintu kecil di sudut barat laut Masjid. Wadah air ini disebut sebagai Padasan Kiai lantaran khusus dipergunakan oleh keempat Kiai jika akan menunaikan ibadah shalat untuk kemudian memasuki masjid melalui pintu di sampingnya. Dua bejana lainnya disebut sebagai wadah Banyu Kejayan dan Banyu Panglepasan yang diyakini punya khasiat tertentu. Material organik yang berupa penutup atap dihadirkan ke dalam bangunan secara ritualistik dan diperbarui secara berkala. Sejak pemasangan awalnya, kehadirannya telah ditetapkan bersifat sementara sehingga dipersiapkan untuk suatu saat nanti akan diganti. Sirap dan welit dipergunakan juga untuk menandai bangunan utama dan bangunan pendukung. Makam, Witana, Masjid dan Pasalinan adalah empat serangkai bangunan utama yang ditengarai dengan atap sirap kayu jati. Di antara keempatnya, Makam memiliki hirarki tertinggi lantaran sirap untuk bangunan ini semua harus diganti baru saat Buka Sirap, sedangkan ketiga bangunan lainnya menggunakan komponen campuran antara sirap baru dan sirap bekas dari Makam yang telah dibersihkan dan diperbaiki. Bubungan jurai bangunan Makam juga harus senantiasa diganti saat pembaruan atap berkala ini. Dimensi komponen ini adalah yang paling panjang di 194 antara bubungan jurai yang lain sehingga memudahkan saat harus dipotong ujungnya yang biasanya lebih mudah lapuk untuk kemudian dipasang pada bangunan lain. Gerbang memiliki perlakuan khusus. Bangunan ini semula beratap welit namun belakangan diganti dengan atap sirap. Saat ritual Buka Sirap, dua sisi atap di keempat gerbang ini juga diganti tapi menunggu setelah keempat bangunan utama dibongkar atap lamanya. Hampir semua sirap dan bubungan jurai untuk gerbang adalah komponen bekas yang didapat dari Makam yang telah diseleksi dan diperbaiki. Bangsal Peziarahan dan bangunan penutup sumur memiliki kedudukan yang paling rendah di antara bangunan beratap sirap. Karena kedua bangunan yang berukuran cukup besar ini dianggap sebagai bangunan tambahan, keduanya tidak mengikuti siklus pembaruan empat tahunan tapi menyesuaikan dengan kondisi kerusakan yang dialami. Cadangan sirap bekas yang disimpan cukup memadai jika sewaktu-waktu dipergunakan untuk memperbaiki kedua bangunan tersebut. Atap welit yang dipergunakan untuk menutup atap bangunan-bangunan penunjang diganti pada saat Memayu. Semua welit dan anyaman belarak diganti, tak ada yang dipertahankan. Mengingat waktu penggantian welit hanya setengah hari, maka urutan pembongkaran dan pemasangan atap alang-alang ini tidak begitu kentara. Atap Paseban lazimnya dibongkar pertama kali dan diselesaikan terakhir kali. Bukan hanya karena bangunan tempat kedudukan Sep ini memiliki hirarki tertinggi di antara bangunan beratap alang-alang, tapi juga karena bangunan ini memiliki dimensi yang terbesar sehingga memerlukan penanganan yang jauh lebih lama ketimbang bangunan lainnya. Bale Keprinci dan Jinem Wadon diperlakukan dengan teknis yang berbeda lantaran keduanya dianggap sebagai bangunan baru. Welit di kedua bangunan ini dipasang lembar demi lembar langsung pada usuk dan reng sehingga tidak mempergunakan rangken atau rangka bambu sebagaimana pada bangunan welit lainnya. 195 Mustaka Masjid adalah pengecualian. Hiasan puncak ini adalah satu-satunya komponen bangunan berbahan tanah liat yang dipasang di atas bangunan. Pucuk atap Masjid. Masjid Kramat Buyut Trusmi yang beratap tajug bersusun tiga memiliki hiasan puncak berupa mustaka yang terbuat dari tanah liat bakar. Mustaka ini terdiri atas dua bagian yang bisa dilepas dengan mudah. Bagian bawah berbentuk piramida terpancung dengan hiasan relief timbul berbentuk bunga di keempat sisinya. Hiasan berbentuk serupa daun berpilin yang sedang tumbuh mencuat dari keempat sudut elemen ini. Bagian atas berbentuk seperti permata dengan penampang persegi yang mengecil di bawah dan di atas. Dengan puncak berbentuk serupa kuncup bunga, bagian atas ini juga dihias dengan bentuk daun berpilin yang tumbuh di tiap sudutnya. Secara teknis, bentuknya yang rumit dengan delapan sulur mencuat dan ragam hias floral lainnya memang lebih mudah dibentuk dengan tanah liat yang plastis tersebut. Di kawasan Cirebon, bangunan-bangunan kuna yang beratap lancip atau tajug memang lazim menggunakan mustaka tanah liat, baik pada bangunan keagamaan seperti pada berbagai masjid dan langgar seperti Masjid Pajalagrahan, Langgar Ageng Kanoman dan Langgar Alit Kasepuhan, ataupun bangunan nonkeagamaan seperti pada Mande Pandawa Lima di Kraton Kasepuhan dan Bale Manguntur di Kraton Kanoman (Nugroho, 2012). Mustaka tersebut lebih dipandang sebagai hiasan puncak (finial) yang bersifat dekoratif yang menghias ketimbang sebagai bagian dari atap yang menaungi. 5.3.2. Asal Muasal Material sebagai Jejaring Sumber Dalam kunjungan terakhir saya ke Trusmi tanggal 4 Mei 2016 yang lalu, seorang kemit menceritakan tentang upaya dia untuk menanam beberapa pokok pohon jati di pemakaman sebelah utara tembok Kramat. Dia berharap agar hal ini dapat terjadi terus-menerus sehingga ketersediaan cadangan kayu untuk Buka Sirap dapat dipenuhi. Selain di lingkungan Kramat Buyut Trusmi ada beberapa petak lain yang juga ditanami pohon jati untuk memasok kebutuhan Kramat. Abdul Hamid, seorang tukang muda yang sudah belasan tahun terlibat dalam pembangunan di Kramat mengantarkan saya ke sebuah tempat di tengah desa yang disebutnya sebagai 196 hutan wakaf. Di sudut hutan ini terdapat masjid dan sumur tua yang dikenal warga sebagai Sumur Wasiat. Menurutnya, dari cerita yang didapat dari ayahnya, dulu ada hutan wakaf yang lebih luas yang juga ditanami jati untuk kepentingan Kramat. Akan tetapi, karena perselisihan kepemilikan tanah antar ahli waris akhirnya tanah yang semula telah diwakafkan secara lisan ini dibagi-bagi antar ahli waris. Pada dasarnya, jati dipahami sebagai pohon yang tumbuh di Kramat, atau di hutan wakaf yang secara konseptual merupakan perluasan dari Kramat. Jati yang merupakan pohon tahunan menjadi bagian dari lansekap kramat dalam waktu yang relatif lama sebelum ditebang dan diproses menjadi komponen bangunan. Hingga saat ini kalau kita melihat lingkungan Kramat Buyut Trusmi, maka yang mendominasi panorama adalah tegakan-tegakan jati tersebut. Atap welit dan sirap menyembul di sela-sela pokok jati dan di balik tembok merah bata pelingkup kompleks Makam. Meskipun sekarang sedikit sekali kebutuhan kayu jati yang dapat dipenuhi oleh lingkungan Kramat dan hutan wakafnya, tapi pemandangan yang terbentuk dari jalinan antara bangunan beratap sirap dan pepohonan jati di sekitarnya membangkitkan gambaran bahwa jati pada dasarnya berasal dari tempat tersebut. Alang-alang tak terlalu sulit dijumpai di Desa Trusmi dan sekitarnya. Akan tetapi, Memayu memerlukan jumlah alang-alang yang jauh lebih besar ketimbang yang tersedia di Desa tersebut. Biasanya alang-alang ini didapatkan dari Desa Singaraja yang terletak di kabupaten Indramayu yang sangat dekat dengan pesisir Laut Jawa. Keterkaitan material dan sumbernya dapat bersifat historis. Pada tahun 1970an, sebatang dahan menjatuhi mustaka di puncak Masjid yang terbuat dari tembikar yang mengakibatkan kerusakannya. Para pengelola Masjid dan Makam memutuskan untuk menggantinya dengan mustaka yang terbuat dari tembaga yang saat itu mulai populer, dengan pertimbangan bahwa material baru ini lebih awet sehingga mampu bertahan lebih lama ketimbang mustaka yang terbuat dari gerabah. Mustaka lama yang rusak disimpan di Bale Pasalinan di sisi pintu menuju ke Makam. Dalam pawai Ider-ideran menjelang Memayu berikutnya, mustaka lama ini diikutkan untuk diarak 197 keliling kampung. Suatu insiden terjadi ketika ada seorang anak kecil berada di dekat itu yang pingsan dan kemudian meninggal tak lama kemudian. Para pengelola Kramat menafsirkan hal ini sebagai isyarat agar puncak Masjid kembali dihiasi dengan mustaka dari tanah liat dan bukan tembaga. Berdasar adat setempat, mustaka baru haruslah dibeli di Kampung Panjunan. Berasal dari kata jun atau ajun yang berarti wadah air dari tembikar, Panjunan adalah tempat pembuat jun sejak sebelum Kraton Cirebon berdiri, sehingga memiliki otoritas historis sebagai tempat asal muasal pembuatan benda-benda dari tanah liat bakar ini. Permasalahan dalam penggantian mustaka dari Panjunan ini mengemuka lantaran sekarang tak ada lagi pembuat gerabah di Panjunan. Para pemuka Trusmi bermusyawarah untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya disepakati kompromi adat bahwa mustaka tersebut dipesan di Desa Jamblang yang saat ini masih memiliki pengrajin gerabah, akan tetapi tempat pembelian mustaka tersebut haruslah tetap dilakukan di Panjunan. Jejaring sumber material ini seperti memetakan relasi antara Trusmi dengan lingkungan pendukungnya. Jati di bukit dan alang-alang di pesisir adalah dua sumber yang secara terus menerus dihidupkan jalinannya dalam keterkaitan spasial. Sementara, Panjunan, desa sangat tua penghasil gerabah membentuk jalinan temporal dengan masa silam kawasan Cirebon. 5.4. Konsep Konstruksi Pada Buka Sirap tahun 2014, dilakukan eksperimentasi dalam menyiapkan sirap-sirap tersebut. Pengait yang berupa dua pasak kecil yang menancap pada sisi dalam sirap diganti bahannya. Biasanya batang kecil ini terbuat dari kayu, tapi saat itu diganti dengan bambu. Pasak bambu ternyata memiliki keuntungan pada keliatan bahannya dan lebih mudah pembuatannya. Akan tetapi material baru ini memilik kekurangan dari segi kembang susut bahannya yang relatif lebih besar ketimbang kayu. Penggantian bahan ini jelas didasrkan pada cara pandang yang menekankan 198 pada tujuan teknis untuk membuat konstruksi bangunan yang lebih kuat dan mengefisienkan tenaga kerja. Sementara sirap dipersiapkan secara teknis, tradisi penggantian sirap itu sendiri lebih menekankan pada konstruksi yang bersifat simbolis. Ketika bilah-bilah sirap disucikan sebelum dipasang pada bangunan Makam terjadi proses transformatif dari suatu komponen yang semula dibuat dengan tujuan teknis yang berkaitan dengan kekuatan dan keawetan menjadi elemen yang menekankan pada kesucian. Sirap yang pernah menjadi bagian dari konstruksi bangunan Makam meyerap energi positif dari doa-doa yang dipanjatkan para Kemit dan peziarah, mengendapkan berkah dari Allah yang dikaruniakan melalui kebaikan leluhur yang dimakamkan di situ. Ketika konstruksi atap dibongkar, sirap pun dipilah menjadi tiga kategori, yakni sirap siap dipasang pada bangunan baru, sirap yang memerlukan penyesuaian dimensi dan bentuk untuk dipasang pada bangunan baru atau sirap yang akan disimpan sebagai benda yang menyandang berkah. Konstruksi (sebagai kata benda) dapat dipahami sebagai penggabungan sejumlah komponen fisik menjadi suatu kesatuan yang relatif stabil. Dalam suatu konstruksi cara dan pola penggabungan tertentu diterapkan untuk mencapai tujuan dari keutuhan tersebut. Suatu konstruksi dapat memiliki tujuan-tujuan yang bersifat: a) teknis yang berkaitan dengan kestabilan, kekokohan dan keawetan, b) simbolis untuk mengungkapkan makna tertentu atau mewakili gagasan tertentu, dan c) teknis maupun simbolis. Bagian ini akan mendalami berbagai tujuan dari konstruksi yang terbentuk di Kramat Buyut Trusmi beserta perwujudan fisiknya untuk memahami konsep-konsep yang melandasinya. ‘ 5.4.1. Konstruksi sebagai Susunan Praktikal Dengan dukungan dana dari para pengusaha batik di Trusmi, pada pertengahan tahun 1960-an tak lama setelah Peristiwa Kerusuhan G30S 1965, Ki Ahmad selaku Sep pada saat itu memutuskan untuk memperbesar bangunan Masjid 199 di Kramat Buyut Trusmi. Respon mendukung dan menentang dari berbagai pihak bermunculan termasuk dari kalangan pengelola Kramat sendiri. Di antara perdebatan yang muncul saat itu adalah apakah Masjid ini akan diperluas saja, atau diperluas dan ditinggikan. Kedua pilihan ini memiliki implikasi konstruksi yang berbeda. Ki Ahmad ternyata sangat mendukung pilihan kedua yang membuat Masjid ini bukan hanya menampung jamaah yang lebih banyak tapi juga tampil lebih menonjol di lingkungan tersebut. Dengan peninggian ini, puncak masjid menjadi titik yang paling tinggi di seluruh Desa. Bangunan serambi yang menempel pada sisi timur bangunan utama Masjid juga turut ditinggikan. Tiang-tiang masjid yang semula berbentuk silinder dengan ketinggian sekitar tiga meter diganti menjadi tiang persegi dengan ketinggian hampir dua kali lipat. Para pembangun saat itu mempertimbangkan untuk memanfaatkan struktur serambi sebanyak mungkin. Secara umum atap bangunan ini tak berubah tapi keenam tiang persegi yang menopang atap tersebut harus ditinggikan. Guna memanfaatkan komponen struktur utama tersebut, tiang-tiang kayu jati ini disambung masingmasing dengan balok sepanjang satu meter. Sambungan ini kemudian ditutup dengan papan kayu di keempat sisinya. Terbukti sambungan ini masih kokoh hingga sekarang. Pengembangan konstruksi dengan tujuan efisiensi dan perkuatan seperti ini juga dijumpa dalam skala yang lebih rinci pada bebagai bangunan lainnya. Bangunan Paseban dan Jinem Lanang yang merupakan bangunan beratap welit yang paling besar di Kramat Buyut Trusmi semula memiliki usuk yang terbuat dari bambu. Belakangan, usuk-usuk bambu ini diganti dengan balok-balok kayu sehingga menjadi lebih kokoh. Dengan pertimbangan untuk menguatkan konstruksi rangka atap maka beberapa tahun yang lalu kerapatan usuk kayu ini ditambah. Konstruksi rangka kayu dipandang sebagai elemen yang relatif panggah sehingga diupayakan untuk tetap kokoh dan stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika sebagian dari rangka ini telah lapuk, terutama jika pelapukan terjadi pada 200 ujung-ujungnya maka dilakukan pemotongan pada bagian tersebut sehingga sisanya masih dapat dipergunakan untuk bangunan lain. Tiang-tiang silinder yang semula menyangga atap bangunan utama di Masjid kemudian dipindahkan untuk memperkuat berbagai bangunan lain setelah disesuaikan ukurannya. Penggunaan komponen struktur dari bangunan lain yang telah disesuaikan ukurannya tidak dipandang mengurangi derajat bangunan tersebut. Witana yang diyakini sebagai bangunan asal muasal menggunakan tiang kayu di keempat sudutnya yang berasal dari bangunan Makam. Lubang-lubang bekas purus pada bagian atas tiang tersebut dengan jelas menunjukkan cirinya sebagai komponen bekas. Karena ukuran Witana yang relatif kecil maka komponen bangunan lain yang lebih besar dengan mudah dapat dimanfaatkan di sini. 5.4.2. Konstruksi sebagai Simbol Simbol yang terungkap dalam konstruksi di Kramat Buyut Trusmi memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah simbol-simbol yang bersifat filosofis untuk mengungkapkan nilai-nilai luhur kepada khalayak. Karakteristik yang kedua berkaitan dengan status sosial suatu kelompok yang berafiliasi dengan konstruksi tersebut. Keseluruhan proses dan komponen dalam pembaruan atap sirap dan welit di Kramat Buyut Trusmi bersifat ritualistik, sehingga masing-masing komponennya menyandang nilai simbolis sebagai objek sakral. Simbol ini tidaklah bersifat representasional dengan melekat hanya pada salah satu aspek komponen tersebut, seperti letak, bentuk dan warna, tapi bersifat menyatu dengan objeknya. Ketika dipasang di Makam, suatu keping sirap misalnya, menjadi bagian dari bangunan yang dimuliakan dalam jangka waktu tertentu. Keterkaitannya dengan Makam tidaklah abadi karena dalam jangka waktu delapan tahun berikutnya keping tersebut akan dilepas untuk menjadi bagian dari bangunan lain atau disingkirkan karena tak layak lagi untuk dimanfaatkan. Masyarakat tampaknya jauh lebih antusias untuk turut melepas komponen tersebut ketimbang menyimpan bekas sirap yang 201 dengan mudah dapat diminta ke para pangelola Kramat. Berebut mereka menyentuh komponen-komponen konstruksi saat dilepas dan dibawa keluar secara beranting dari halaman makam. Bagitu pula saat membawa masuk secara beranting pula komponen sesudah disucikan di Balong Pakulahan untuk dipasang. Momen membangun dan mengurai bangunan adalah momen terpenting dalam persinggungan antara kahalayak dengan komponen bangunan. Berebut melepas komponen tersebut bukan berarti merayakan pelapukan tapi merayakan klimaks “pengabdian” suatu komponen kanstruksi dalam menaungi bangunan yang diyakini menyandang berkah. Mengambil bagian aktif dari momen-momen ini walaupun sekedar menyentuhnya menjadikan mereka partisipan yang membuat ulang bangunan-bangunan tersebut. Bubungan bangunan Makam yang digantungkan dan mustaka Masjid yang diturunkan adalah bagian dari penekanan status simbolis komponen-komponen spesial tersebut. Keduanya menyandang peran untuk mewakili keseluruhan bangunan dan proses pembangunan ulangnya. Melepas dan memasangnya kembali menjadi ungkapan awal dan akhir proses pembaruan konstruksi ini. Saat bergabung ke dalam suatu entitas bangunan, beberapa komponen pada bangunan tertentu dianggap memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tak sepantasnya komponen tersebut dipasang ulang pada bangunan yang lain. Bekas pintu Kiai yang terletak di sudut barat laut Masjid yang dipasang di Jinem Wadon dianggap tak pantas oleh masyarakat sehingga kemudian dipindahkan ke ruang pawestren atau tempat shalat putri. Sementara, bekas pintu bangunan Makam yang dipergunakan untuk menggantikan pintu Bale Pasalinan dianggap baik. Begitu pula bekas bubungan Makam yang istimewa yang dipindahkan ke Bangsal Peziarahan di depannya. Peran simbolis yang kedua berkaitan dengan identitas individu atau kelompok dan status yang ingin didapatkannya. Peninggian atap dan bangunan Masjid yang selesai pada tahun 1968, misalnya, yang disponsori oleh para pengusaha batik membentuk dinding yang tinggi di antara ruang shalat dan serambi yang memungkinkan pemasangan pintu penghubung yang juga tinggi. Pintu tinggi yang 202 menjadi akses utama ke ruang shalat dari serambi ini diukir dengan ragam hias berbentuk bunga dengan kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad. Di bawah ragam hias bunga ini terdapat hiasan berbentuk sayap garuda (lar) yang serupa dengan lambang Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dengan memodifikasi sedikit pada bagian ekornya. Para donatur pembangunan ini tampaknya ingin meninggalkan jejak kontribusi mereka pada Kramat. Ukiran tiang-tiang masjid dan di gapura barat Kramat mengingatkan kita pada ragam hias yang dijumpai pada batik khas Cirebon yang banyak diproduksi di Trusmi. Motif harimau dan naga sangat populer dalam beberapa motif batik tersebut dijumpai pada komponen-komponen konstruksi ini. 5.4.3. Konstruksi sebagai Sarana Pertukaran Dengan mengambil bagian dalam pengembangan, pembangunan ulang dan perbaikan pada bangunan-bangunan di Kramat Buyut Trusmi seseorag mengambil bagian dalam proses pertukaran. Mereka menyumbangkan kecakapan, tenaga, waktu, material dan dana dalam proses-proses tersebut dan sebagai gantinya akan mendapatkan berkah. Berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa dan mengalir kepada manusia di antaranya melalui orang-orang yang dicintai dan dekat dengan-Nya. Ki Buyut Trusmi yang diyakini masyarakat sebagai wali dan pewarta Islam yang paling awal adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan demikian dapat menjadi sarana menyalurkan berkah tersebut. Membangun dan mendukung pembangunan dengan mengkontribusikan berbagai ragam sumber tersebut diyakini menjadi sarana untuk mendapatkan berkah sebagai gantinya. Para tukang dan semua pengobeng yang terlibat dalam Buka Sirap dan Memayu jelas mengharapkan berkah tersebut setelah menyumbangkan ketrampilan dan tenaga mereka. Penyelenggaraan kedua ritual ini secara terus menerus menjamin kesinambungan pertukaran dan dengan demikian perolehan berkah ini. 203 Para donatur yang memiliki kemampuan finansial yang besar ingin berperan lebih besar dan berharap berkah yang lebih pula. Mereka dapat berperan mendukung atau bekerja sama dalam pengembangan fisik Kramat yang diprakarsai oleh pengelolanya, seperti pada pengembangan Masjid yang dilakukan Kiai Ahmad setengah abad silam. Untuk pembangunan yang lebih sederhana, sejumlah donatur ini berinisiatif untuk melakukan rehabilitasi yang sepenuhnya mereka kerjakan. Masyarakat Trusmi menyebut bantuan ini sebagai “paketan” karena rancangan, bahan dan tenaga semua dalam satu “paket” yang ditangani oleh donatur dengan nyaris tanpa keterlibatan pengelola. Paketan terakhir yang disumbangkan pada tahun 2015 adalah perbaikan Masjid yang meliputi pemasangan ubin keramik berukuran 30 x 30 sentimeter pada seluruh dinding dalam ruang shalat, pemasangan hiasan tepi pada dinding keramik tersebut berupa kaligrafi yang terbuat dari kayu serta pemasangan sepasang AC di kiri-kanan mihrab masjid ini. Kesemua komponen tersebut dapat dipasang dan dibongkar lagi dengan mudah sehingga dapat ditambahkan pada bangunan tersebut tanpa banyak mengubah konstruksi dasarnya. Semula lantai bangunan Makam terbuat dari pasangan bata. Pada tahun 1950 seorang donatur menyumbang tegel abu-abu untuk dipasang. Sekitar empat puluh tahun berikutnya atas prakarsa donatur juga lantai tegel ini diganti dengan keramik. Namun demikian, berbeda dengan pemasangan keramik di Masjid, pemasangan ubin di makam ini tak dapat dilakukan dengan sistem paketan karena hanya para Kiai, Kunci dan Sep yang boleh memasukinya. Para pengelola Kramat ini menjadi tukang yang memasang ubin tersebut. Ubin menjadi pilihan utama para donatur mengingat mudahnya pelaksanaan dan dapat dikenali dengan mudah. Dengan demikian, ubin tampaknya menjadi komponen tak panggah yang baru yang berupa material industrial. 204 5.5. Rangkuman Konsep Secara konseptual Kramat Buyut Trusmi pertama-tama dipahami sebagai tempat asal-muasal yang menjadi landasan eksistensial keberadaan masyarakat dan Desa Trusmi. Asal-muasal ini berkembang menjadi sesumber bagi perkembangan permukiman di sekitarnya, dan bagi kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang luas. Tempat ini juga mengalami transformasi dari kediaman menjadi peziarahan tanpa meninggalkan sejumlah sifat-sifat dasarnya sebagai kediaman. Dalam kaitannya dengan pembaruan bangunan, konsepsi waktu yang terbentuk menjalin antara pemahaman diakronis dan sinkronis dengan mempertimbangkan alam, sistem kalender, simbolisme dan sosial. Perubahan material secara alami direspon melalui tindakan membangun ulang yang diperhitungkan berdasarkan perhitungan waktu yang kompleks tersebut. Material yang dipergunakan dalam berbagai proses pembangunan di Kramat Buyut Trusmi diterapkan dengan mempertimbangkan asal-usul material dan karakteristik bangunan yang diperbarui. Jejaring material mengungkapkan hubungan natural-kultural dengan sumber-sumber material. Penerapan material pada bangunan mempertimbangkan sifat-sifat dasar dari bangunan sebagai kediaman dan sifat-sifat alami material. Konstruksi atau proses membangun pada tataran fisik diperlakukan sebagai suatu susunan praktikal untuk kepentingan fungsional. Pada tataran simbolik, konstruksi mengungkapkan nilai-nilai kepantasan untuk tiap komponen bangunan. Pada tataran spiritual, membangun adalah sarana mempertukarkan potensi menjadi berkah sehingga konstruksi menjadi “alat” konversi dalam pertukaran tersebut. 205 BAB 6 MENGEMBANGKAN TEORI ARSITEKTUR DENGAN KETIDAK-PANGGAHAN Beberapa kali Klassen (1990: 45) menegaskan bahwa “... architecture is made”. Dengan pernyataan ini dia menggarisbawahi sifat bendawi arsitektur. Namun demikian, dia juga menjabarkan bahwa untuk merealisasikan yang karya bendawi tersebut setidaknya pembuatnya perlu untuk memiliki gagasan tentang bentuk dan gambaran keterlibatan manusia nanti setelah arsitektur terwujud. Khasanah bentuk arsitektur bersifat akumulatif, sedangkan keterlibatan manusia yang akan menggunakan bersifat antisipatif. Sepanjang proses pembuatan arsitektur, sang pembuat menjalani proses mental mengembangkan khasanah bentuk yang telah dia himpun sambil menggambarkan bagaimana pengguna akan mengalami bangunannya. Tanpa memisahkan gambaran tentang pengguna dan pembuat, Norberg-Schulz (2000) meyakini bahwa guna adalah yang pertama kali dirumuskan. Guna yang digagaskannya berupa tindakan fundamental dan menyeluruh yang tak terfragmentasi sebagaimana unit-unit fungsi yang diprogramkan dalam arsitektur modern. Guna yang paling asasi adalah ketika manusia—baik secara individu maupun kelompok— tiba di suatu tempat yang dipahaminya memiliki makna yang mendalam sehingga dia memutuskan untuk berkediaman di tempat tersebut. Arsitektur dibangun untuk mewujudkan pemahaman tentang tempat tersebut sehingga dia dapat mentransformasikannya sebagai tempat berkediaman. Kajian tentang Kramat Buyut Trusmi pada bab-bab sebelumnya memberikan gambaran serba cakup tentang fenomena berkediaman secara kolektif dan publik, serta fenomena membangun tempat berkediaman tersebut secara berulang yang 206 melibatkan komponen-komponen tak panggah dalam bangunan-bangunan yang dibuat. Kedua fenomena ini dilandasi dengan pemahaman tentang tempat sebagai pijakan eksistensial yang perlu untuk dihadirakan, tentang waktu sebagai jalinan berbagai kerangka yang memberi makna pada kesementaraan, tentang material sebagai sesumber membangun yang perlu untuk dijaga keterkaitannya, serta tentang konstruksi sebagai strategi dalam membangun tempat berkediaman yang memberi makna bagi perulangan membangun dan pembaruan bangunan. Ketidakpanggahan yang melandasi praktik berarsitektur dan lingkungan yang dibentuk dalam praktik tersebut meniliki karakter relasional yang kuat. Pembangunan terus menerus bukan hanya menjadikan bangunan senantiasa diperbarui, tapi hubungan sosial, fisis dan spiritual juga selalu diperbarui agar pembuatan berulang ini bermakna. Untuk itu, bab ini diawali dengan pembahasan tentang pelbagai relasi yang berkembang dalam praktik berarsitektur di Kramat. Dalam upaya untuk menjawab permasalahan kajian tentang pengembangan teori sistem arsitektur dengan menekankan pada ketidakpanggahan, maka bab ini membahas ketiga komponen sistem sebagaimana dikerangkakan oleh Kruft (1994) dan dijabarkan oleh Klassen (1990) dan Norberg-Schulz (2000), yakni, aspek praktikal dalam tindakan membangun dan bangunan, aspek sosial dalam keterlibatan manusia di dalam bangunan, serta aspek estetis yang berupa kontemplasi atas nilai luhur yang melandasi kedua aspek yang lain. Dengan menekankan pada ketidakpanggahan, maka fenomena berarasitektur di Kramat Buyut Trusmi dapat diabstraksikan sebagai sistem arsitektur yang terdiri atas: mewujudkan arsitektur sebagai pengembangan aspek teknis, memanfaatkan arsitektur sebagai pengembangan aspek sosial dan menghayati arsitektur sebagai pengembangan aspek estetis. Penjabaran tentang ketiga aspek ini menjadi bagian utama dari bab ini. 207 Guna mempertajam kontribusi teoretik yang diajukan, bab ini diakhiri dengan diskusi pembandingan dengan teori-teori lain yang sejenis. Dengan diskusi ini diharapkan pengembangan teori yang diajukan dapat diidentifikasikan ranah dan nilai pentingya secara lebih baik. 6.1. Relasi dalam Berarsitektur dengan Ketidakpanggahan 6.1.1. Relasi Fisik Ketidakpanggahan pertama-tama adalah sifat yang melekat pada aspek fisik suatu benda. Dengan daya tahan yang relatif terbatas, suatu benda dipandang memiliki sifat ini secara kentara. Penurunan kualitas fisik yang berupa penampilan, kekuatan dan kewetan suatu bahan atau komponen bangunan adalah indikator ketidakpanggahan yang paling mudah dikenali. Dalam kaitannya dengan arsitektur, penurunan kualitas fisik ini menjadikan suatu komponen bangunan perlu untuk ditangani secara khusus dengan diperbaiki, diperkuat atau bahkan harus diganti. Penanganan yang relatif kerap terhadap komponen tak-panggah ini mengintensifkan relasi fisik relasi antara material dengan sumbernya serta relasi antara komponen bangunan dengan bangunan secara keseluruhan. Arsitektur atau dalam wujud bendawi yang paling konkretnya berupa bangunan dibuat manusia untuk dipergunakan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dibandingkan dengan benda-benda lain buatan manusia seperti pakaian, alat-alat pertukangan dan perabot rumah tangga, bangunan berkuran lebih besar dan tersusun atas lebih banyak komponen. Manusia mengubah sesumber yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan dan harapannya. Secara teknis dengan perangkatperangkat pertukangan, pokok kayu pada tegakan pohon dapat ditebang sebagai gelondongan, kemudian dipotong dengan bangun prismatis sebagai balok, lalu diketam rapih sebagai papan yang rata. Pemahaman tentang karakteristik material, 208 teknik membangun dan nilai simbolis bangunan yang diwujudkan akan menentukan apakah sebatang balok kayu akan menjadi tiang penyangga, gelagar yang mengubungkan tiang, atau sunduk yang mengencangkan rangka pada bangunan tertentu. Setiap material yang membentuk komponen bangunan yang dirangkai memiliki asal-muasal yang menjadi bagian dari pemahaman terhadap bahan bangunan, komponen konstruksi dan bangunan yang akan diwujudkan. Asal-muasal ini ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Alang-alang, secara umum, adalah tanaman gulma bagi petani dicabut sebagai bagian untuk mempersiapkan lahan pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan bahan bangunan. Dengan melakukan Memayu secara berkala peningkatan kualitas fisik atap dilakukan dalam tindakan yang sama dengan peningkatan kualitas lahan pertanian. Kayu jati berasal dari tanaman budi daya. Pembaruan atap dengan sirap kayu jati mengintensifkan hubungan antara bangunan dan hutan-hutan jati budi daya yang dimiliki oleh Kramat sebagai bagian dari sistem lingkungan. Relasi sesumber material alang-alang dan kayu jati ini menghadirkan kembali momen asali pembukaan padang ilalang untuk pertanian dan permukiman Desa Trusmi serta pengembangan budi daya kayu jati pada tahapan berikutnya. Kedua material ini sekarang lebih banyak didapatkan dari pembelian. Relasi asasi tersebut di atas dihidupkan melalui tindakan-tindakan simbolis yang terkait dengan pemanfaatan alang-alang dan kayu. Alang-alang yang liar didomestikasi agar menjadi bagian dari lingkungan perdesaan dengan diarak keliling desa, yang saat ini menjadi prosesi yang lebih banyak diikuti warga ketimbang penggantian atap alangalang itu sendiri. Komponen-komponen konstruksi kayu jati yang bersifat hasil budi daya setempat, diintegrasikan dengan unsur kesetempatan yang lain yakni air di Balong Pakulahan dengan cara dimandikan terlebih dahulu di kolam yang disucikan tersebut sebelum dipasang pada bangunan. 209 Mustaka masjid yang terbuat dari tanah liat memiliki hubungan kesejarahan yang khusus. Pada awalnya, mustaka ini dibuat di Desa Panjunan yang semula adalah tempat pengrajin gerabah sebagaimana dikenali dari toponimnya. Karena penggantian komponen esensial ini setara dengan pembangunan di masa awalnya maka penggantian mustaka ini harus dijalankan dengan tetap menjaga hubungan dengan Desa Panjunan. Relasi fisik yang penting berikutnya adalah relasi antara bangunan dan komponen bangunan. Setelah material diproses menjadi komponen bangunan, maka kompenen tersebut disusun menjadi bangunan. Di Kramat Buyut Trusmi komponen konstruksi bangunan secara umum dibagi menjadi komponen baru yang dipersiapkan untuk dipasang pada bangunan, serta komponen bekas yang dipasang pada suatu bangunan setelah sebelumnya menjadi bagian dari bangunan lain, sering kali dilakukan dengan memodifikasi komponen tersebut untuk menghilangkan bagian yang lapuk dan usang. Ketiga bangunan utama yang beratap sirap memiliki pola hubungan yang berbeda dangan komponen bangunan penyusunnya. Bangunan Makam atau Kabuyutan memiliki kedudukan tertinggi yang diwujudkan dengan kebaruan komponen bangunannya. Sirap dan semua komponen konstruksi yang dipasang di Kabuyutan adalah baru sehingga bangunan ini memiliki relasi yang paling langsung dengan sesumber material. Sebagai bangunan peribadatan, Masjid ini memiliki hubungan khusus dengan para donatur. Banyak amal atau nadhar dalam bentuk pemugaran bangunan di kompleks Kramat ini dilaksanakan pada bangunan Masjid. Penambahan elemen dekoratif, komponen konstruksi hingga perluasan bangunan dilakukan pada bangunan ini. Pemasangan penyejuk ruangan (AC), keramik pelapis dinding dan dekorasi ukiran kaligrafi adalah penambahan yang terakhir terjadi pada tahun 2015. 210 Witana memiliki pola hubungan fisik antara komponen bangunan dan tapaknya yang khas. Bangunan yang diyakini sebagai tinggalan tertua Pangeran Walangsungsang yang ada sejak mula berdirinya kompleks ini justru paling banyak menggunakan komponen bekas yang pernah dipasang pada bangunan lain. Semua tiang tepinya memiliki lubang untuk sunduk tapi tak ada balok sunduknya yang jelas menunjukkan bahwa tiang-tiang ini pernah menjadi bagian dari bangunan lain. Beberapa usuknya memiliki lubang berderet karena semula adalah bagian dari rangka pagar. Bubungan jurai Witana yang relatif pendek sering kali diganti dengan bekas bubungan jurai Kabuyutan. Tampaknya yang paling asli dari Witana adalah kedudukannya di dekat Balong Pakulahan dan dimensinya yang sangat kecil yang mengisyaratkan ketika entitas sosial Trusmi masih sangat terbatas. Ketidakpanggahan melestarikan dan menghidupkan relasi-relasi fisik tersebut. Memperbarui atap secara berkala dengan bahan-bahan bangunan yang tak panggah dan teknik membangun yang memudahkan penggantian tersebut menjadikan relasi dengan berbagai sesumber material senantiasa terjalin. Ritual yang menyucikan dan melibatkan komponen-komponen tak-panggah pada bangunan-bangunan di Kramat Buyut Trusmi menjadikan relasi dengan sesumber tersebut senantiasa memiliki makna yang lebih mendalam dari pada persyaratan teknis semata. 6.1.2. Relasi Sosial Ketidakpanggahan material memerlukan penanganan bangunan yang relatif kerap. Perbaikan dan penggantian komponen bangunan di kompleks Kramat Buyut Trusmi agar tetap dapat bertahan ini dilaksanakan secara ekstensif dengan melibatkan khalayak yang sangat luas. Pekerjaan bersama ini diselenggarakan dalam relasi sosial tertentu dan setelah dilaksanakan berulang dalam jangka panjang menjadi pembentuk relasi sosial berikutnya. Hubungan timbal balik antara penanganan fisik dan relasi sosial terjadi sangat intensif yang melekat pada praktik berarsitektur di Kramat. 211 Relasi sosial di Kramat Buyut Trusmi sangat khas serta berkaitan erat dengan keberadaan bangunan dan lingkungan binaan di tempat tersebut. Relasi ini membentuk dan dibentuk oleh arsitektur di tempat tersebut. Saat seorang pengelola Kramat Buyut Trusmi harus diganti, maka diselenggarakanlah “pemilihan umum” yang melibatkan seluruh laki-laki dewasa warga Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Lebih dari sekedar tempat atau fasilitas, Kramat ini adalah suatu lembaga sosial. Hampir semua Kramat yang berpangkal pada ketokohan seorang wali memberikan kewenangan khusus kepada mereka yang diyakini sebagai keturunan sang wali atau keturunan mereka yang memiliki kedekatan langsung dengan wali tersebut. Di Trusmi tak ada seorangpun yang dapat mengklaim diri sebagai keturunan Ki Buyut Trusmi atau keturunan murid-murid terdekatnya yang dimakamkan bersama-sama di Kabuyutan. Berdasar pemungutan suara yang didahului dengan pendaftaran calon layaknya pemilihan kepala daerah seorang pengelola Kramat dipilih. Pola hubungan yang tidak mengandalkan ikatan primordial ini tampak sangat “modern” meskipun menyandang bias gender. Secara teoretis setiap warga memiliki kesempatan yang sama, bahkan karir sebagai kiai atau kunci tak serta merta melempangkan jalan menjadi seorang Sep, sebagaimana Sep Tonny yang belum pernah menjabat sebagai kiai atau kunci sebelumnya. Kedekatan sosio-spiritual dengan Kramat biasanya dianggap masyarakat sebagai hal yang paling dihargai. Setelah terpilih menjadi pengelola Kramat, para tokoh masyarakat ini menyandang kedudukan khusus yang terungkap dalam keseharian mereka di tempat peziarahan tersebut. Secara visual kedudukan ini dapat dikenali dari pakaian yang mereka kenakan saat berdinas di Kramat. Seorang Kiai, Kunci atau Kemit mengenakan pakaian yang khas yang dengan mudah akan dikenali oleh siapapun yang berziarah ke tempat tersebut. Mereka berperan sebagai pengelola kunjungan, pengelola tempat dan pengelola sumbangan yang setiap hari akan disirkulasikan. Sebagai pengelola kunjungan mereka mengarahkan peziarah dengan keperluan 212 tertentu untuk melakukan tindakan tertentu di salah satu bagian Kramat. Mereka juga mengkoordinasikan pemanfaatan dan perawatan tempat tersebut. Para pengelola ini menerima sumbangan dalam berbagai bentuknya setiap hari, tapi sekaligus juga mendistribusikannya kepada khalayak dan peziarah. Dalam kaitannya dengan pembentukan bangunan dan lingkungan binaan di Kramat Buyut Trusmi, pembaruan atap saat Memayu dan Buka Sirap adalah saat untuk menegaskan dan menghidupkan pola-pola hubungan sosial ini dalam prosesi yang dilaksanakan secara berkala. Dalam Memayu, relasi yang bersifat egaliter sangat kentara sehingga setiap partisipan terlibat dalam penyiapan, penurunan dan pemasangan welit. Setiap warga berperan sebagai anggota dari “keluarga besar Ki Buyut Trusmi” yang bersama sama memperbaiki rumah leluhur mereka. Memayu melestarikan dan dilestarikan dalam pola solidaritas horisontal ini. Dalam Buka Sirap, relasi sosial yang bersifat hierarkis mengemuka. Kecakapan, pengalaman dan kemampuan masing-masing kelompok dalam masyarakat menentukan jenis, intensitas dan derajat partisipasi dalam upacara yang memiliki dimensi teknis dan ritual ini. Para pengelola Kramat dengan kapasitas spiritual mereka, para tukang dengan kecakapan teknis mereka, para pengobeng dengan kesungguhan mereka, para donatur dengan kemampuan finansial mereka, berkontribusi dengan pola dan cara yang berbeda dalam penyelenggaraan Buka Sirap. 6.1.3. Relasi Spiritual Kramat Buyut Trusmi dapat dipahami sebagai simpul spiritual, tempat banyak orang dengan berbagai minat, kepentingan dan harapan datang untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Memayu dan Buka Sirap yang melibatkan komponenkomponen tak panggah tersebut adalah peristiwa penting untuk mengintensifkan simpul spiritual yang mempertemukan kalangan yang sangat luas dengan keberkahan sebagai motivasi utama mereka. 213 Spiritualitas ini adalah salah satu ungkapan Islam populer yang dihayati oleh masyarakat luas tanpa selalu mendapatkan legitimasi tekstual. Di Kramat Buyut Trusmi, beberap Sep adalah tokoh thariqah atau olah spiritual dari ordo Qadiriyah wa Naqshabandiyah bahkan ada yang menjadi mursyid atau guru yang memiliki legitimasi membimbing dan silsilah spiritualnya menerus hingga Nabi Muhammad. Akan tetapi keterkaitan dengan thariqah ini bukanlah suatu hal yang diutamakan untuk menunjang reputasi kramat Trusmi sebagai tempat peziarahan. Ki Buyut Trusmi penting untuk didekati dan menjadi tumpuan harapan karena dia adalah seorang wali atau kekasih Allah. Dalam keyakinan populer ini, pemahaman terhadap sistematika teologis tentang status makhluk dan Khalik bukanlah hal yang paling utama. Ketentraman yang dirasakan ketika berada di dekat Kramat memegang peran yang lebih penting dalam memotivasi tindakan mereka untuk mengakrabi dan melibatkan diri dengan lingkungan Kramat. “Medan spiritual” dibentuk dalam berbagai pertukaran. Seorang peziarah meluangkan waktu dan biaya; seorang tukang menyumbangkan kecakapan dan keterampilannya; seorang donatur menyumbangkan beras, kayu atau pertunjukan hiburan saat perayaan di Kramat. Semua hal ini dilakukan untuk melibatkan diri dalam “medan spiritual” dan mendapatkan berkah sebagai gantinya. Berkah yang dapat berupa ketenangan hati, kedamaian hidup hingga kesuksesan bisnis dan ujian sekolah. Dalam peziarahan sehari-hari, perayaan ritualistik mapun prosesi pembaruan bangunan, relasi spiritual ini bersifat sentral. Manusia, arwah dan tempat terjalin dalam relasi yang berujung pada perolehan berkah ini. 6.2. Teori Sistem Arsitektur dengan Ketidakpanggahan Sistem arsitektur sebagai suatu totalitas dengan komponen-komponen yang saling berkait dirumuskan dengan ragam yang sangat banyak dalam berbagai teori (Vibaek, 2014). Di antara sistem arsitektur yang berkembang adalah teori Proses 214 Arsitektur yang diajukan Klassen (1990) dan teori Kehadiran Arsitektur yang diajukan Norberg-Schulz (2000). Kajian tentang ketidakpanggahan yang menonjol dalam praktik di Kramat Buyut Trusmi menjadi hal penting dalam mengembangkan kedua teori tersebut sebagai berikut. 6.2.1. Mewujudkan Arsitektur Mewujudkan arsitektur dipahami sebagai upaya mentransformasikan suatu tempat secara konkret dan bendawi sehingga memiliki karakter figuratif yang dapat dicerap secara inderawi dan dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Dalam membangun secara berulang dengan melibatkan ketidakpanggahan, karakter prosesual dalam mewujudkan arsitektur menjadi sangat menonjol. Kenduri besar yang menandai akhir Buka Sirap, misalnya, di satu sisi menyatakan bahwa proses mewujudkan arsitektur yang diperbarui telah usai. Namun demikian, di sisi lain berarti penanda bahwa proses melapuk dan melekang dimulai. Dalam kaitannya dengan pembentukan tempat yang sekarang disebut sebagai Kramat Buyut Trusmi, upaya mewujudkan ini terjadi pada momen pembangunan awal ketika Ki Buyut Trusmi yang dalam salah satu versi adalah Pangeran Walangsungsang dengan berbagai pertimbangan mengambil keputusan untuk menetap di tempat ini. Keputusan menetap ini kemudian direalisasikan dalam wujud lingkungan binaan tempat kediaman Ki Buyut yang kemudian berkembang menjadi Desa Trusmi yang didasarkan pada pemahaman terhadap tempat berkediaman yang bermakna sekaligus pemahaman terhadap lingkungan setempat. Momen asali ketika Ki Buyut membina suatu tempat yang bermakna sehingga menjadi tempat berkediaman nyata ini dipahami bersifat asasi dalam pembentukan dan pengembangan Kramat beserta Bale Gede dan lingkungan fisik di sekitarnya. Momen ini menjadi tumpuan keberadaan lingkungan Desa Trusmi yang senantias hidup dan berkembang hingga menjadi permukiman padat saat ini. Warga tak lagi membangun dengan atap alang-alang sebagaimana Bale Gede di dekat mereka. Akan 215 tetapi, rumah-rumah kuna beratap welit dan praktik memperbaruinya adalah pemberi makna bagi keberadaan mereka saat ini. Agar keberadaan Kramat dan lingkungannya tersebut berkelanjutan, momen asali ini dihidupkan dalam pembaruan bangunan di Kramat Buyut Trusmi. Penyelenggaraan Memayu dan Buka Sirap tidak dijadwalkan dalam sistem penanggalan tertentu melainkan selalu diputuskan di awal tahun dengan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk situasi temporer yang berkembang saat itu. Dengan selalu menjaga sifat situasional ini, warga Trusmi menghindari prosesi pembaruan bangunan mereka sebagai tradisi yang hanya mengandalkan pada perulangan berkala. Lebih dari sekedar mengulang peristiwa yang terjadi setahun atau empat tahun sebelumnya, tindakan memperbarui bangunan adalah upaya menghidupkan momen awal untuk Mewujudkan Arsitektur sebagaimana dilakukan para tokoh cikal bakal tempat ini. Berkediaman, dengan demikian, bukan tindakan sekali jadi membangun permukiman lalu menghuninya semata. Upaya berkediaman harus senantiasa dihidupkan melalui tindakan Mewujudkan Arsitektur agar semangat dan makna awal dapat terjaga. Penghidupan kembali ini dimungkinkan dengan keterlibatan aspek ketidak-panggahan dalam arsitektur Kramat Buyut Trusmi. Komponen penutup atap yang tak panggah memainkan peran yang instrumental dalam tindakan ini. Penutup atap diganti atau dipindahkan sehingga bangunan mendapatkan keberadaannya yang baru. Ketidak-panggahan tidak dipahami sebagai kelemahan atau kekurangan dalam berarsitektur di Kramat Buyut Trusmi. Aspek ini diterima dan bahkan dirayakan karena dengan ketidak-panggahan tersebut momen asali Mewujudkan Arsitektur dapat terus menerus dihadirkan. Secara sosial, proses mewujudkan arsitektur secara berulang dengan melibatkan warga secara ekstensif ini melebur batas antara pembuat dan pengguna bangunan. 216 Aktivitas fisik dan aktivitas mental antara kedua kelompok ini saling bertumpang tindih. Pemisahan kedua aktivitas inis sebagaimana diajukan Klassen (1990) tidaklah relevan lagi. Pengelola Kramat mewujudkan arsitektur sebagai bangunan spiritual melalui teknik membangun praktikal, sedangkan warga membangun konstruksi fisik dengan mostivasi spiritual. 6.2.2. Memanfaatkan Arsitektur Sebagaimana gubahan musikal yang menjadi nyata ketika diperdengarkan, arsitektur atau tempat berkediaman barulah nyata ketika telah melibatkan manusia yang menggunakannya (Klassen, 1990). Kehadiran manusia bersifat esensial karena tanpanya suatu kediaman tak akan terbentuk. Dalam kerangka Empat Serangkai Heidegger (2001a) yang banyak dirujuk Norberg-Schulz (2000), manusia adalah unsur asasi dari tempat berkediaman yang membangun sekaligus menjadikannya bermakna. Manusia disebut Heidegger sebagai the mortals karena kefanaan dan kesementaraan mereka dalam hidup dan dalam melibatkankan diri dengan arsitektur. Memanfaatkan dalam hal ini dipahami sebagai kehadiran manusia di dalam kediaman tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Dalam kaitannya dengan ketidakpanggahan dan pembaruan bangunan, kemanfaatan ini meliputi kebaikan fisik yang didapat usai pembangunan, kemanfaatan sosial dalam bermasyarakat melalui praktik membangun serta kemanfaatan spiritual yang didapat dengan mengintensifkan hubungan dengan Kramat. Terdapat perbedaan yang mendasar antara cara pandang Norberg-Schulz (2000) dan Klassen (1990) tentang kehadiran manusia tersebut. Klassen membedakan dengan tegas antara pembuat dan pengguna bangunan meskipun keduanya dalam derajat tertentu dapat bertukar peran, khususnya dalam aktivitas mental. Sehingga pembuat berperan sebagai pengguna dan sebaliknya. Sementara, Norberg-Schulz tidak membedakan perbedaan peran antara keduanya. 217 Di Kramat Trusmi peleburan antara keduanya terjadi melalui pembangunan berkala yang melibatkan publik dalam skala yang luas. Setiap orang yang hadir saat Buka Sirap dan Memayu berupaya untuk mengambil bagian seberapapun kecilnya sehingga dapat melibatkan dirinya sebagai pembuat bangunan. Pembauran ini memberikan dampak yang mendalam pada pembauran antara aktivitas membuat dan menggunakan arsitektur, serta refleksi pemahaman yang terjadi dalam praktik berarsitektur di tempat tersebut. Para pengelola Kramat tampil sebagai pembangun utama dalam prosesi Buka Sirap. Pada saat itu, para Kiai dan Kunci yang memiliki kewenangan khusus untuk naik ke atas atap Makam tampil sebagai pembuat bangunan yang didukung oleh para tukang dan khalayak pengobeng. Lebe yang menurunkan dan menaikkan mustaka dari puncak Masjid juga memiliki peran serupa untuk berperan sebagai pembangun utama pada prosesi tersebut. Pada saat Memayu, warga bekerja dengan sigap secara otonom untuk menurunkan welit, menyiapkan dan merangkai welit, serta memasangnya untuk memperbarui atap alang-alang. Para pengelola Kramat nyaris tidak terlibat dalam prosesi yang hanya berlangsung setengah hari ini. Mereka lebih banyak menyibukkan diri mengelola logistik kontribusi warga serta menyiapkan minyak dan kelengkapannya untuk dibawa pulang para pemburu berkah. Sepanjang prosesi ini mereka memerankan diri sebagai pemilik bangunan yang memungkinkan pembangunan terjadi tanpa terlibat langsung menanganinya, atau bahkan menjadi pengguna karena mendapatkan manfaat dari proses dan hasil pembangunan ini. Ketika pengguna adalah pembuat maka pertanyaan tentang tujuan pembuatan menjadi penting untuk diajukan. Membuat bangunan tampaknya bukan lagi terbatas pada tindakan pihak pembuat agar dapat dipergunakan oleh pihak lain yang akan menggunakannya seusai tindakan membuat dinyatakan purna. Keterlibatan ekstensif, lebih dari 500 orang yang saat Buka Sirap memosisikan diri sebagai tukang dan 5000 orang yang berperan sebagai pengobeng, menunjukkan keinginan yang luar biasa 218 untuk dapat mengambil bagian dalam ritus pembangunan ini. Mereka membangun untuk mendapatkan kemanfaatan, dalam hal ini untuk meraih berkah, sehingga pembangunan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dari pemanfaatan. Relasi yang mempertukarkan kontribusi tenaga, waktu luang dan kecakapan menjadi berkah bukan hanya mengundang orang untuk berpartisipasi tapi bahkan telah melebur batas pembuat dan pengguna, serta antara membuat dan menggunakan. Bangunan dibuat terus menerus dengan memperbarui bagian tak-panggahnya, dengan demikian, dapat dipahami lantaran pembuatan adalah salah satu bentuk penggunaan. Pertukaran peran dan pelaku terjadi secara mendasar dan menyeluruh bukan hanya dalam ranah aktivitas mental tapi juga dalam aktivitas fisik. Paradigma pertukaran peran ini juga menjangkau ke pembangunan pada bagian-bagian yang lebih panggah. Pada tahun 2015 ketika dilakukan pemasangan keramik dan ukiran kaligrafi di Masjid, beberapa pengelola Kramat menyebut pembangunan itu sebagai “paketan” yang berarti dibuat sepenuhnya atas prakarsa donatur tanpa melibatkan mereka. Donatur yang sebelumnya adalah warga peziarah mendudukkan dirinya dengan dukungan kemampuan finansialnya untuk menjadi pembuat. Dalam ranah memanfaatkan lingkungan binaan Kramat Buyut Trusmi dapat diidentifikasikan sejumlah pola pemanfaatan, yakni: kemanfaatan fungsional, kemanfaatan sosial, serta kemanfaatan spiritual. Kemanfaatan fungsional berkenaan dengan penyelenggaran aktivitas di kompleks Kramat Buyut Trusmi. Pembagian peran antara para kaum (lebe, ketib, modin dan merbot) yang mengelola Masjid serta kunci, kiai dan kemit yang mengelola Makam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pemanfaatan secara fungsional bangunan Makam dan Masjid. Secara keruangan perbedaan ini lebih samar mengingat aktivitas dan pelaku yang terkait dengan peziarahan dapat melibatkan ruang Masjid. Sebelum disediakan tempat khusus, para 219 perempuan bertirakat menjalani ritus mereka di pawestren atau ruang shalat khusus permpuan. Kiai yang uniknya di Trusmi lebih banyak berurusan dengan peziarahan ketimbang dengan urusan keagamaan memiliki pintu khusus dan tempat wudhu khusus di sudut barat laut Masjid yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam aktivitas ibadah sehari-hari. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan intensifikasi hubungan antar warga dan kerabat Kramat sekaligus pemahaman terhadap struktur sosial yang berkembang. Buka Sirap menegaskan pola-pola hubungan yang bersifat hirarkis dengan pembedaan peran yang tegas antara pengelola Kramat, tukang dan pengobeng. Sementara, Memayu mengembangkan solidaritas horisontal yang egaliter tanpa pembedaan status dan peran yang kentara. Pelestarian tradisi membangun ini dengan demikan memungkinkan warga untuk mewariskan pola hubungan sosial bergand atersebut dari generasi ke generasi secara luas. Kemanfaatan spiritual berkaitan dengan peran Kramat sebagai sarana untuk mendapatkan berkah. Dalam peziarahan dan tirakat yang dilakukan sehari-hari di Kramat masyarakat datang untuk mendapatkan berkah dengan meluangkan waktu di tempat tersebut. Saat Memayu dan Buka Sirap masyarakat memiliki kesempatan untuk mengkontribusikan berbagai potensi yang mereka miliki sehingga mengintensifkan afiliasi sosial mereka dengan Kramat sekaligus mengaktifkan jejaring berkah yang dikembangkan melalui proses pertukaran ini. Kramat menjadi semacam “mesin” pertukaran atau “dapur pengolahan” sesumber yang dimiliki masyarakat agar mereka dapat menuai berkah. Bangunan menyandang peran berganda sebagai lokasi pertukaran dalam mengakomodasi aktivitas sekaligus menjadi objek pertukaran dalam pembangunan berulang. Masyarakat mendapat spiritual benefit atau kemanfaatan spiritual yang berupa berkah, sedangkan Kramat—dengan partisipasi ekstensif masyarakat—mendapat kemanfaatan berupa peningkatan reputasi. 220 6.2.3. Menghayati Arsitektur Keping-keping sirap di Kramat Buyut Trusmi berukuran relatif kecil sehingga seorang dewasa dapat dengan mudah mengangkat 10 keping sekaligus. Akan tetapi, saat Buka Sirap, untuk memindahkan sekeping sirap Kabuyutan yang telah dilepas ke tempat penyortirannya di depan Jinem yang berjarak kurang dari 10 meter diperlukan puluhan lelaki dewasa yang berdiri rapat dan secara beranting memindahkan keping sirap tersebut. Memegang sirap secara langsung dan memindahkannya dari tangan seseorang ke orang yang lain sangat berbeda dengan memandang sirap yang terpasang di atap Kabuyutan dari kejauhan. Dengan sirap berada di tangan, orang dapat mengetahui sifat-sifat fisik keseluruhan keping sirap tersebut yang biasanya hanya terlihat ujung lancipnya saja, menaksir timbangan sirap yang relatif ringan lantaran terbuat dari kayu jati yang relatif muda, menguji kekokohan pasak kecil tempat menggantungya pada reng, meraba barik permukaan atasnya yang berkerak karena cuaca dan membandingkannya dengan sisi bawahnya yang terlidungi. Mereka yang berpengalaman berpartispasi dalam beberapa kali Buka Sirap, selama memindahkan keping ini, dapat dengan mudah menduga apakah sirap tersebut masih layak untuk dipakai pada bangunan lain atau perlu untuk segera disingkirkan. Sambil memindahkan sirap mereka berbincang dengan orang di kiri dan kanannya yang melakukan tindakan serupa. Beberapa hari dengan berganti ganti posisi para pengobeng dan tukang terlibat dalam aktivitas membangun ini. Mereka menyaksikan para Kiai dan Kunci yang bermandi peluh sepanjang hari di atas atap Kabuyutan sambil membantu para pengelola Kramat tersebut untuk menaikkan dan menurunkan komponen-komponen bangunan. Seseorang memahami kedudukannya dalam diferensiasi dan hirarki sosial masyarakat serta tindakan yang pantas baginya melalui praktik membangun ini. Kramat adalah tujuan peziarahan. Setiap kunjungan ke tempat ini pada dasarnya adalah berziarah dan setiap pengguna ruang adalah mereka yang berziarah atau yang melayani peziarah. Kategori sosial seperti lelaki, 221 perempuan, tukang, pengobeng, wong ziarah, wong tirakat, diproduksi dan direproduksi dalam praktik keseharian, ritual dan prosesi membangun di Kramat Trusmi. Dengan memahami bahwa tiap kunjungan ke Kramat pada hakekatnya adalah peziarahan dan tiap tindakan di tempat tersebut adalah bagian dari prosesi peziarahan, berbagai aktivitas di tempat ini dapat dipahami kesejajaran dan kesalinghubungannya. Mendekatkan diri pada arwah Ki Buyut Trusmi dan para kekasih Allah yang dimakamkan di tempat ini—yang pada tahap berikutnya akan mendekatkan mereka kepada Allah—adalah alasan utama peziarahan dalam berbagai bentuknya di Kramat Buyut Trusmi. Bagi para peziarah, berdoa yang dilakukan secara verbal saja terlalu abstrak untuk dapat membantu mereka merasakan kedekatan dan kehadiran para arwah tersebut dalam kehidupan. Bermalam berhari-hari dalam tirakat, menanak nasi ketika Muludan, mengikat welit ke rangken di saat Memayu adalah berbagai wujud dari upaya mengkonkretkan dan mengintensifkan rasa kedekatan tersebut. Dengan melibatkan raga mereka dalam berbagai praktik yang diselenggarakan di Kramat mereka menjalin kedekatan spiritual. Sebaliknya kedekatan spiritual ini memotivasi mereka untuk melibatkan lebih lanjut keberadaan ragawi mereka dalam bentuk-bentuk peziarahan yang lebih intensif. Para Kemit semula adalah peziarah biasa yang kemudian membulatkan tekad untuk mengabdikan diri mereka. Dalam kaitannya dengan tempat, ruang dan bangunan, para peziarah tersebut membangun pemahaman tentang Kramat Buyut Trusmi melalui praktik peziarahan mereka dalam arti yang luas. Simbolisasi kesakralan, segregasi keruangan, hingga teknik-teknik ketukangan dipahami melalui berbagai praktik tersebut. Menghayati Arsitektur, dalam kajian ini, dimaknai sebagai tindakan memahami arsitektur melalui keterlibatan ragawi yang bermotivasi spritual. Meskipun memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat, pemahaman ini tidak didapatkan melalui permenungan, pengasahan nurani dan olah rohani semata. Menghayati Arsitektur 222 yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman yang didapatkan melalui tindakan langsung di dalam suatu lingkungan binaan dan keberadaan raganya pada tempat tersebut. Cukup mudah dipahami bahwa bertafakur di Jinem atau di bangunan lain di sekitar Makam dan Masjid adalah suatu tindakan spiritual. Akan tetapi di Trusmi, menggergaji kayu dan mengamplasnya adalah olah spiritual juga yang menjadi bagian dari Menghayati Arsitektur. Kramat Buyut Trusmi dan lingkungan sekitarnya dapat dikatakan sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Akan tetapi, Kramat ini sama sekali bukanlah tempat yang senyap, terlebih pada saat penyelenggaraan upacara dan peringatan tertentu seperti Mamayu, Buka Sirap dan puncak keramaiannya adalah pada akhir peringatan Maulud Nabi. Keramaian orang menjajakan dagangan dan hingar-bingar berbagai tontonan dan hiburan mendominasi jalan dan ruang terbuka utama di Desa Trusmi Wetan dan Kulon. Kesibukan “duniawi” seperti itu sebagaimana aktivitas teknis ketukangan memiliki dimensi spiritual ketika secara keruangan dan temporal berkaitan dengan Kramat sehingga merupakan bentukbentuk Penghayatan Arsitektur. Secara leksikografis, kata “hayat” yang merupakan kata dasar dari “menghayati” bermakna “hidup” atau “kehidupan”, serta “mengalami” atau “merasakan” sesuatu di dalam batin (KBBI Daring, 2016). Dengan demikian “menghayati” dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai menginternalisasikan pengalaman dalam kehidupan yang bersifat lahiriah menjadi pemahaman yang bersifat batiniah. Menghayati Arsitektur melampaui batas phronesis yang merupakan pemahaman intelektual dan techne yang merupakan pemahaman teknikal karena melibatkan dimensi spiritual yang justru dicapai dengan keterlibatan ragawi. Praktik jasmaniah menjadi sarana untuk mencapai pengalaman rohaniah. Dan sebaliknya, pengalaman rohaniah memotivasi untuk melakukan tindakan jasmaniah. 223 6.3. Diskusi Komparasi Teori: Ketidak-panggahan di antara yang terurai dan yang tak stabil Diskusi yang bersifat komparasi teori dilakukan dengan tujuan untuk menguji sejauh mana teori yang diajukan dalam kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan arsitektur. Hal ini dilakukan dengan mengkomparasikan teori tersebut dengan teori lain yang memiliki keserupaan sehingga dapat mempertajam teori yang diajukan. 6.4.1. Pemilihan Teori Kebaruan teori yang dirumuskan di atas dilakukan melalu pembandingan dengan teori sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya. Teori tersebut dipilih berdasarkan: a) Keterkaitan geografis: Teori yang dipilih memiliki latar belakang wilayah geografis kepulauan dengan basis masyarakat agraris sehingga memiliki tingkat keakraban dengan lingkungan alam dan material organik sebagaimana yang dijumpai di Trusmi. b) Keterkaitan tematis: Teori yang dipilih menekankan pada peran material tak-panggah yang berasal dari bahan organik sebagaimana sirap dan alang-alang yang dipergunakan di Trusmi. c) Keterkaitan tipe bangunan dan tindakan: Teori yang dipilih berfokus pada kajian bangunan yang berkaitan dengan pemujaan yang melakukan pembangunan ulang sebagai tindakan ritualistik. Berdasarkan kriteria tersebut dipilih teori yang diajukan oleh Nitschke (1979) tentang pembentukan dan penguraian simpul sebagai asal muasal arsitektur di Jepang yang juga merupakan negara kepulauan di Asia Timur dengan hubungan yang erat dengan Asia Tenggara (Kumar, 2009). Simpul dipahami sebagai sistem tanda pertama yang dikembangkan dari bahan tak-panggah. Simpul berperan di antaranya untuk menandai wilayah, membentuk bangunan dan membentuk simbol kepercayaan. 224 Dengan demikian tempat dan bangunan yang terbentuk memiliki hubungan yang erat dengan ritual di tempat tersebut. Teori kedua diajukan oleh Domenig (2014) sebagai bagian dari disiplin ilmu “Antropologi Keruangan” yang dikembangkannya dengan Indonesia sebagai wilayah kajiannya. Sebagaimana teori Nitschke (1979) yang meyakini bahwa penciptaan arsitektur pada dasarnya adalah tindakan ritualistik, Domenig mengembangkan teori evolusi arsitekturnya dengan menekankan pada struktur yang dibangun untuk kepentingan ritual sebagai asal-muasal arsitektur. 6.4.2. Teori 1: Shime (simpul) sebagai Asal-Muasal Arsitektur Nitschke (1979) mengembangkan suatu kajian yang komprehensif yang meliputi berbagai aspek kebudayaan Jepang untuk mengajukan teori bahwa asal muasal penciptaan kediaman manusia adalah pembuatan simpul (shime) dari material organik yang tak-panggah. Tindakan merangkai yang menghimpun sejumlah komponen ke dalam suatu kesatuan pertama kali diwujudkan dalam bentuk simpul. Simpul ini diyakini berkembang berikutnya sebagai bangunan, sistem tanda, dan bahkan sistem kepercayaan. Dia mengajukan hipostesis tentang proses evolusi dalam pembuatan simpul ini sebagai berikut: Manusia Asia Timur di awal peradaban berupaya untuk membuat penanda atas wilayah yang dikuasainya. Pada tahap awal evolusinya, penanda wilayah ini dibuat menggunakan teknik yang paling sederhana dengan bahan yang paling mudah dibentuk yakni membuat ikatan dan simpul dari rumput, ilalang atau semak. Tindakan awal ini diyakini sebagai sistem penanda visual yang pertama diciptakan manusia, sehingga dari penanda ini berkembang sistem-sistem yang lebih kompleks seperti aksara dan simbol-simbol keagamaan. Dengan membuat tanda ini manusia mentransformasikan sepetak lahan dari khaos yang terjadi karena ketiadaan kuasa atanya menjadi kosmos yang tertata. Kuasa atas wilayah yang tertata itu kemudian dipersonifikasikan menjadi dewa yakni Musubi atau dewa pengikat yang dipuja di tempat tersebut. 225 Lantaran penanda awal tersebut terbuat dari material yang tak-panggah maka secara berkala penanda kedudukan tersebut harus diperbarui untuk melestarikan klaim atas wilayah, kuasa dan status kedewataan. Pembaruan penanda secara berkala ini kemudian berkembang menjadi mitos penciptaan dunia dan upacara yang terkait dengannya. Dengan demikian terdapat pertalian erat antara Kuni-Umi atau penciptaan dunia dan Matsuri atau pembaruan dunia. Keduanya dipahami dalam konteks spasial dan temporal. Konteks spasial dalam kaitannya dengan pendefinisian ruang dan orientasi ruang; sedangkan temporal dalam kaitannya dengan transformasi anatara khaos menjadi kosmos. Pembaruan simpul ini meliputi beberapa tipe proses: a) dengan menguraikan untuk kemudian mengikatnya kembali, b) dengan menambahkan material baru pada simpul lama, c) dengan memusnahkan yang lama dan membuat yang sama sekali baru, dan d) dengan menyingkirkan yang lama dan membuat yang sama sekali baru. Dalam kaitannya dengan dewa yang dipuja pada suatu bangunan tak-panggah terdapat beberapa pola upacara pembaruan: a) Kuil Kediaman. Dewa berkedudukan pada bangunan yang semula terbuat dari bahan tak-panggah, sehingga untuk memperbarui dewa tersebut harus dipindahkan kedudukannya pada bangunan lain yang setara. Hal ini dapat dijumpai pada pembaruan Kuil Ise di Nara yang diselenggarakan dalam waktu 8 tahun pada tiap interval 20 tahun. b) Kuil Temporer. Dewa berkedudukan di tempat lain, biasanya di bukit atau di laut. Dewa tersebut diundang untuk hadir sementara dalam suatu upacara. Suatu struktur dibuat sebagai kedudukan sementara mereka selama upacara berlangsung. dimusnahkan. 226 Seusai upacara struktur tersebut c) Gabungan. Dewa berkedudukan di kuil. Saat kuil tersebut diperbarui dibuatkan struktur temporer untuk kedudukan dewa tersebut. Seusai pembaruan kuil, struktur temporer tersebut dihancurkan. d) e) Gambar 6.1. Ragam simpul dalam tradisi Jepang (Nitschke, 1979) Lebih lanjut dalam membangun argumen tentang proses evolusi bangunan dan ritus pembaruan bangunan, Nistchke mengajukan tentang empat tahap pengembangan bangunan suci yang terkait dengan relasi antara bumi dan langit. a) Tahap Pertama adalah Kekacauan. Bumi dan Langit tak terbedakan bercampur aduk menjadi satu. b) Tahap Kedua adalah Tatanan dengan Langit di atas Bumi. Kuil dibangun dengan pola kediaman manusia. Atap dengan penanda puncak yang menjangkau langit berdiri di atas struktur panggung berpilar kokoh yang memijak bumi. 227 c) Tahap Ketiga adalah Perpisahan. Bumi menuju ke bumi dan Langit menuju ke langit. Jagad raya dipahami berdasarkan pemahaman manusia atas wilayah yang mereka kuasai ketimbang sebaliknya. Shime menjadi bagian dari bumi. d) Tahap Keempat adalah adalah Langit. Melalui tindakan simbolik atau tepatnya melalui tindakan membuat bangunan. Pada saat festival langit kembali hadir mengakrabi “Bumi” 6.4.3. Teori 2: Tektonika dengan Prinsip Parastatic Complementing Dalam mengkaji asal muasal arsitektur di Indonesia, Domenig (2014) membangun argumen bahwa arsitektur berpangkal pada aktivitas dan pemahaman ritualistik. Para pemukim awal membuka lahan dengan membabat pepohonan dan belukar. Dalam banyak tradisi, sebelum dibuka lahan tersebut sudah dihuni atau dikuasai oleh makhluk halus. Para pembuka hutan mengupayakan agar tercapai “kesepakatan” dengan makhluk tak kasat mata tersebut sehingga setelah hutan tersebut dibuka menjadi kediaman para pamukim kemudian menyelenggarakan upacara untuk mengundang kembali arwah yang semula tinggal di situ. Ritual membuka lahan adalah esensial dalam penciptaan ruang. Wujud yang lebih konkret dari tempat pemujaan ini berupa altar dengan berbagai bentuknya. Altar ini dapat berupa panggung atau tonggak yang dihias dengan aneka rupa dedaunan dan tetumbuhan segar. Hiasan ini ditujukan untuk mengundang arwah agar singgah yang dapat diperkuat secara dinamis dengan bau, warna dan gerak. Ragam altar dengan penguat hiasan yang lebih statis diwujudkan dalam bentuk atap mencuat, tangga menjulang kelangit atau tonggak yang dibalik. 228 Gambar 6.2. Altar yang terbuat dari bambu dengan hiasan dedaunan yang terpisah (kiri) atau menyatu (kanan) (Domenig, 2014) Altar dan hiasannya yang diletakkan di tempat terbuka dapat dikaitkan dengan rumah. Orang membuat rumah yang memiliki jalur untuk mengaitkan dengan altar dan bentuk-bentuk yang menyerupai altar tersebut agar arwah yang turun berkenan untuk singgah lebih lama di rumah mereka. Jalur dan gerbang untuk menyambut kedatangan arwah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia Timur. Atap menjulang dibuat sebagai pengganti tangga ke langit untuk memudahkan kunjungan arwah. Banyak sekali daerah yang memiliki beragam hiasan bubungan sebagai transformasi dari elemen tetumbuhan sebagai penghias altar agar arwah tertarik untuk berkunjung. Atap dengan bubungan yang menjoraok jauh atau menjulang tinggi memainkan peran yang sama dengan atap berhias tersebut. 229 Dari relasi antara altar yang panggah dan tetumbuhan yang tak-panggah ini berkembanglah arsitektur dengan berbagai ragam wujudnya. Dalam teori Domenig (2014) dualitas ini bertahan dalam bentuk susunan tektonika yang dipahaminya sebagai suatu keseluruhan sistem struktur yang harmonis ketimbang sebagai sambungan-sambungan individual. Sistem struktur ini memiliki prinsip yang diistilahkannya sebagai parastatic complementing (Domenig, 2014). Dalam prinsip parastatic complementing ini, suatu susunan tektonika terdiri atas sistem berganda yang berbeda yang acapkali terdiri atas bagian yang kokoh dan yang tidak kokoh. Bagian tak kokoh ini dapat terbentuk karena proporsi atap yang menjulang atau menjorok sehingga tak stabil, atap yang berupa lembaran tanpa rangka penunjang yang memadai, hiasan ujung atap yang dapat dibongkar pasang, hiasan ujung atap yang menggambarkan dedaunan penghias altar, dan penggunaan bahan tak-panggah pada bagian tertentu. Domenig (2014) meyakini bahwa tektonika berganda berkaitan dengan prinsip “perjenjangan-pertentangan” (hierarchical opposition) yang dapat dipergunakan untuk memahami tatanan sosial sampai susunan tektonika. Dia berargumen lebih lanjut bahwa dalam kaitannya dengan susunan fisik dapat dipergunakan metafora pohon yang terdiri atas bagian yang batang pohon yang stabil dan kokoh serta cecabang dan dedaunannya yang ringan, tak stabil dan tumbuh. 6.4.4. Diskusi Komparasi Teori Kedua teori yang disajikan di atas memiliki keserupaan dalam lingkup. Lingkup temporal keduanya berpangkal dari masa ketika manusia pertama kali menyatakan keberadaan secara spasial melalui penandaan ruang. Pembukaan lahan dan membangun tanda dengan bahan tak-panggah yang berasal dari tetumbuhan adalah tindakan yang diyakini menjadi asal muasal penciptaan arsitektur. Struktur mula ini berkembang secara evolutif ke dalam berbagai wujud berikutnya dengan tetap menyandang karakteristik dasarnya sebagai bangunan yang memiliki komponen tak-panggah baik secara metaforis maupun riil. 230 Lingkup spasial kedua teori ini juga meliputi kawasan yang luas. Nitschke (1979) mengkaji keseluruhan kepulauan Jepang, sedangkan Domenig (2014) merangkum kepulauan Nusantara. Konsekuensi dari keluasan ruang dan waktu ini menjadikan kedua teori tersebut dirumuskan secara general dan lintas wilayah. Shirazi (2014) menyebut pendekatan ini sebagai “latitudinal phenomenology” yang memungkinkan pengkaji mengembangkan amatan tentang satu tema fenomenologis pada banyak bangunan dengan melintasi ruang dan waktu ketimbang menekuni satu bangunan secara mendalam. Keuntungan dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk membangun generalisasi pada satu tema namun kehilangan kedalaman pada suatu bangunan. Kajian tentang Kramat Buyut Trusmi mengambil pendekatan yang disebut Shirazi (2014) sebagai “longitudinal phenomenology”. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan pengkaji secara ragawi yang intensif pada suatu tempat atau bangunan. Generalisasi dilakukan melalui pengembangan wacana teoretik ketimbang melalui pengkajian banyak bangunan secara parsial. Dengan cakupan periode yang panjang, berawal dari masa awal yang dikonstruksikan secara hipotetis, kedua teori ini memahami benda dan praktik yang ada sekarang seperti Kuil Ise, Perayaan Gion Matsuri, Tongkonan Toraja dan Sanggah Bali dalam mata rantai evolusi. Runtun perubahan yang linear ini memberikan pemahaman akan keutuhan suatu entitas kultural dalam jangka yang sangat panjang seolah tak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Domenig (2014) bahkan memandang negatif kehadiran agama-agama besar dunia di Indonesia dan pengaruh kultural yang menyertainya. Di samping populasinya yang sangat besar, Jawa yang menjadi ajang pertemuan peradaban dan agama besar secara terus menerus nyari sepenuhnya absen dari kajian Domenig. Untuk konteks kepulauan besar seperti Indonesia yang dilintasi pelayaran dunia, terbentuknya isolasi seperti itu terasa tidak realistis. Kajian tentang ketidak-panggahan dalam arsitektur di Kramat Buyut Trusmi melibatkan sepenuhnya berbagai faktor. Kehadiran ajaran Islam dan ritual yang 231 menyertainya, keterlibatan para pengusaha batik setempat dan dinamikanya, serta merebaknya wisata ziarah dalam dasawarsa terakhir ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Desa Trusmi dan Kramat yang menjadi jantung kehiupan spiritualnya. Arsitektur berinteraksi dengan berbagai aspek realita tersebut, menanggapi dan memengaruhi faktor-faktor tersebut. Dengan lingkup yang luas, kedua teori tersebut tak mendalami keterlibatan pelaku dalam tindakan membangun dan memanfaatkan objek yang dibangun tersebut. Para pendeta, peziarah dan khalayak partisipan ritual mungkin memiliki perhatian, minat dan pengetahuan yang berbeda. Keragaman keterlibatan dan pelakunya ini dipahami secara rinci pada kajian ini sehingga teori yang diajukan lebih mendekati realita sosio-spiritual yang berkembang. Shime atau simpul yang diyakini merupakan tindakan mula membuat bangunan terungkap secara terbatas di Kramat Buyut Trusmi. Penerapan teknik simpul ini tampak jelas saat merangkaikan alang-alang menjadi welit menerapkan teknik simpul, begitu pula saat menjalin welit pada rangken dan memasang rangken pada rangka atap. Selebihnya, kompleks Kramat Trusmi menerapkan prinsip yang sangat berbeda. Sirap dipasang dengan kait yang tidak melibatkan proses mengikat dan menguraikan ikatan. Rangka bangunan juga disusun dengan prinsip yang sangat berbeda. Komponen balok dengan purus berlubang yang khas di Jawa dijumpai di semua bangunan di tempat ini. Kait dan purus-lubang jelas bukan simpul meskipun memiliki karakteristik yang mudah dilepas-pasang juga. Bangunan-bangunan beratap sirap di Trusmi memiliki hirarki yang lebih tinggi ketimbang yang beratap welit. Ada kemungkinan pengembangan hipotesa baru bahwa masyarakat Trusmi memandang bahwa sirap adalah perkembangan lebih lanjut dari alang-alang yang dipasang dengan teknik simpul, sehingga memperkuat pendopot bahwa simpul memang lebih tua ketimbang teknik-teknik yang lain untuk membuat bangunan. 232 Dalam kaitannya dengan kedudukan objek sakral selama proses pembangunan ulang, di Trusmi tidak dijumpai adanya objek suci yang harus dipindahkan saat bangunan diperbarui. Hal ini terjadi kerena pembaruan bangunan bersifat parsial sehingga tidak ada saat ketika bangunan itu musnah sama sekali. Kesakralan hanya diungkapkan sebatas penyucian komponen bangunan dan kekhususan orang-orang yang mengerjakan pemasangannya. Secara substansi metafora pohon yang memiliki dualitas yang bertentangan sebagaimana teori parastatic complementing yang diajukan Domenig (2014) ini dapat dipergunakan untuk memahami tektonika di Kramat Buyut Trusmi. Teori tersebut dapat diterapkan untuk menjelaskan bagian landasan yang panggah dan atap yang tak-panggah dan senantiasa diperbarui. Pembaruan atap dengan demikian dapat dipahami sebagai peremajaan pohon itu sebagaiman penggantian tetumbuhan segar yang menghiasi altar asali yang dibahas di awal kajian Domenig tersebut. Pembaruan dalam hal ini dipahami bersifat alami sebagaimana daun yang gugur dan kemudian bersemi sementara pokok pohon tetap tegak berdiri. Dalam prosesi Memayu di Trusmi terdapat relasi yang lebih intensif lagi antara membuka lahan dan mengganti atap. Membuka lahan di tempat tersebut dikisahkan sebagai mengubah padang alang-alang menjadi permukiman sedangkan Memayu adalah memasang atap alang-alang yang baru. Dengan demikian tindakan membabat alang-alang sebagai upaya manusia untuk membentuk keteraturan atas alam liar diikuti langsung dengan pengendalian elemen liar tersebut menjadi bagian bangunan yang sepenuhnya tertata dalam jalinan welit dan susunan atap. Sirap kayu jati memiliki sifat yang berbeda. Pohon jati di Jawa bukanlah tanaman endemik yang tumbuh liar tapi dibudidayakan oleh manusia. Sehingga sirap jati adalah buah dari keteraturan yang telah dibentuk manusia sejak penanamannya. Penggunaan jati secara berulang dengan demikian melestarikan keteraturan yang telah dikembangkan sebelumnya. Secara lebih khusus, relasi Trusmi dengan Gunung Jati yang kompleks menegaskan keterikatan mereka dengan Sunan yang menyandang 233 nama Jati ini yang diungkapkan secara simbolis melalui penggantian sirap jati di Mande Trusmi di kompleks Astana Gunung Jati tiap windu. 234 BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN Keterlibatan aspek ketidak-panggahan dalam bentuk pembangunan berulang di Kramat Buyut Trusmi memiliki landasan dan pengaruh yang fundamental. Lebih dari sekedar perbaikan teknis, pembangunan berulang ini menghadirkan momen awal keberadaan lingkungan ini sehingga arti pentingnya dapat dihayati kembali. Alih-alih menuturkan legenda, warga Desa Trusmi dan ribuan lainnya yang mengafiliasikan diri dengan tempat ini melakukan tindakan nyata dengan memperbarui bangunan untuk menghidupkan momen awal Desa Trismi. Secara teoretik, tradisi pembangunan berulang dengan material tak-panggah memiliki pengaruh yang mendalam. Pada tataran landasan filosofis, tradisi ini memberikan gambaran yang lebih intensif yang mewujudkan pemikiran Heidegger tentang Kediaman Empat Serangkai yang merupakan landasan keruangan keberadaan manusia (Mitchell, 2015), bukan hanya lingkungan fisik dan penggunaannya, 7.1 Ketak-panggahan untuk Hadirkan Asal Muasal Penghulu Masjid Agung Kraton Kasepuhan Cirebon mengisahkan saat saya mengunjungi Masjid tersebut bulan Mei 2016, “Seusai membangun Masjid Agung Demak para Wali Sanga ke Cirebon untuk membangun Masjid Agung Cirebon. Sekali lagi Sunan Kalijaga membuat saka tatal untuk Masjid ini”. Saka tatal adalah tiang yang terbuat dari serpihan-serpihan kayu (tatal) yang dengan karamah Sunan Kalijaga dan izin Allah dijadikan tiang kayu yang kokoh menopang kedua bangunan terbesar dan teringgi pada zamannya tersebut. Tatal yang berupa material limbah takpanggah yang biasanya tercerai-berai itu dengan ajaib dihimpun dan diwujudkan 235 menjadi elemen konstruksi yang tegar menopang atap Masjid dan panggah beratus tahun. Masjid Demak dan Masjid Cirebon memiliki kisah ajaib yang dituturkan turun-temurun tentang seorang wali yang mengubah limbah tak-panggah menjadi komponen konstruksi yang panggah. Kapasitas spiritual dan kecakapan teknis yang menyatu pada diri seorang pemuka agama seperti Sunan Kalijaga memungkinkan transformasi tersebut yang diikuti dengan penciptaan bangunan monumental yang mengesankan. Legenda ini menegaskan bahwa awal penciptaan adalah momen yang sangat penting dan bermakna sebagai landasan keberadaan suatu tempat, dalam hal ini kota Demak dan kota Cirebon, lebih dari sekedar bangunan Masjid. Tempat Dan monumen, keduanya adalah entitas yang konkret yang saling mencerminkan. Kota Cirebon dapat dipahami sebagai ekstensi dari Masjid Agung sedangkan Masjid Agung adalah kondensasi dari Kota. Keduanya saling menandai. Bukan dalam relasi yang absatrak seperti dalam semiotika tapi dalam relasi yang nyata. Kramat Buyut Trusmi memiliki relasi yang serupa dengan Desa Trusmi. Pusat memperluas dirinya sehingga menjadi teritori yang lebih besar. Pola ini ditandai dengan Kramat dan rumah-rumah kuna yang menjadi satelitnya. Alih-alih mewariskan legenda sebagaimana kedua masjid agung tersebut, Kramat Buyut Trusmi memiliki tradisi “ajaib” yang dilaksanakan dengan bersungguh sungguh secara turun-temurun untuk melestarikan arti penting momen awal penciptaan tersebut sebagai landasan yang bermakna bagi keberadaan Desa mereka. Dalam Memayu dan Buka Sirap mereka memperbarui secara terus menerus Masjid, Makam dan bangunan-bangunan lain di Kramat Buyut Trusmi. Lebih dari sekedar narasi verbal, kedua prosesi ini menjadikan momen penciptaan selalu hadir dalah kehidupan dengan semua warga dapat mengambil bagian. Tampaknya lebih dari sekedar kebetulan bahwa Masjid Demak dan Masjid Cirebon dibangun oleh Sembilan Wali, sedangkan Makam Ki Buyut Trusmi dipugar terus menerus oleh sembilan orang pengelolan Kramat yakni Sep, empat Kunci dan 236 empat Kiai. Dengan berpakaian serba putih, kesembilan orang itu selama delapan hari berada di atas atap Makam untuk memugar selama prosesi Buka Sirap seolah mementaskan kembali kisah tentang para Wali yang membangun monumen. Dengan memperlakukan sebagian komponen bangunan sebagai bagian takpanggah, orang-orang Trusmi menjadikan ketidak-panggahan sebagai hal yang esensial dari Kramat Buyut Trusmi yang memiliki berbagai tujuan: a) Secara teknis dengan pembangunan berulang bertujuan agar mereka mendapatkan kualitas bangunan yang lebih baik. Bagian yang bocor diperbaiki, bagian yang lapuk dan lekang diperbaiki atau jika tak lagi layak diganti. b) Secara sosial prosesi pembangunan berulang ini bertujuan untuk menegaskan kembali peran masing-masing anggota masyarakat serta memperbarui semangat kebersamaan dan afiliasi mereka dengan Kramat. c) Secara spiritual tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan langkah nyata bagi mereka untuk memanjatkan doa melalui kerja agar meraih berkah yang diharapkan senantiasa. Praktik berkesinambungan ini dapat dipahami sebagai ungkapan dari konsep mendasar tentang tempat, waktu, material dan membangun. Kramat Buyut Trusmi dipahami sebagai tempat cikal bakal yang menjadi jejak awal keberadaan Desa Trusmi yang selalu dihidupkan dalam ritus membangun ulang. Penggunaan komponen tak-panggah memungkinkan pembangunan ini terus menerus dilakukan sehingga masyarakat dapat memperbarui keterlibatan dan pemahaman mereka tentang tempat yang bermakna mendalam ini. Waktu di Kramat Buyut Trusmi dipahami sebagai alur jamak yang berkaitan secara kompleks. Pelapukan alami, siklus agrikultur, kalender keagamaan dengan landasan konsepsi waktu yang berbeda terjalin dalam penentuan jadwal Memayu dan Buka Sirap. Kedua prosesi ini merangkum aspek ritual, kultural dan natural menjadi momen “kelahiran kembali” bangunan-bangunan di Kramat dalam pembaruan tersebut. 237 Material menduduki posisi sentral dalam praktik membangun ulang ini. Jejaring material dan proses penyiapannya mewujudkan relasi Empat Serangkai secara nyata. Jenis material berkaitan status kompleks Kramat sebagai hunian parexcellence sehingga tak sepantasnya diperlakukan sebagai kuburan. Tumpukan, rangka dan anyaman merupakan basis bagi pembentukan bangunan yang menjadikan konsep Semper (1989) secara nyata. Sedangkan distribusi material ke dalam bangunan mempertegas hirarki dan relasi antar bangunan. Sedangkan Konstruksi yang merupakan proses merangkai komponen bangunan menjadi sarana membangun pemahaman konsep filosofis, sosial dan teknis melalui pengalaman praktikal. Pelaksanaan konstruksi secara massal, repetitif dan ritualistik menjadikan prosesi Memayu, Buka Sirap dan pengembangan bangunan memiliki arti penting dalam melestarikan, menegosiasikan dan menginovasikan tradisi. 7.2 Process dan PresenceArsitektur yang Hidup Rumusan ontologis dwelling atau tempat berkediaman sebagaimana diajukan dengan radikal oleh Heidegger menginspirasi banyak teorisi dan arsitek, antara lain Juhanni Pallasmaa, Peter Zumthor, Dalibor Vesely, Stephen Holl dan Kenneth Frampton (Sharr, 2009), untuk mengembangkan teori dan karya yang bertujuan untuk mewujudkan berkediaman yang bermakna dan akrab dengan kehidupan manusia. Norberg-Schulz (2000) dan Klassen (1990) adalah di antara teorisi yang mengembangkan filosofi tersebut menjadi teori arsitektur yang komprehensif atau menjadi “system architecture” dalam istilah Vibaek (2014). Gagasan dan teori tersebut sebagian besar bertumpu pada arsitektur sebagai hasil suatu proses ketimbang sebagai produk yang secara terus menerus diciptakan sebagaimana di Kramat Buyut Trusmi. Kajian terhadap arsitektur dan praktik yang menjadi bagian inheren dari arsitektur di Trusmi mengembangkan wacana dan teori yang lebih inklusif dengan melibatkan aspek-aspek ketidak-panggahan. Komponen-komponen sistem arsitektur didefinisikan berdasar teori The Presence of Architecture dari Norberg-Schulz (2000) dan The Process of Architecture 238 Klassen (1990) yang dikembangkan dengan melibatkan ketidak-panggahan dalam arsitektur, yang terdiri atas: a) Mewujudkan arsitektur dipahami sebagai upaya merealisasikan pemahaman terhadap arsitektur secara fisik menjadi tempat berkediaman yang nyata dan sebaliknya praktik mewujudkan arsitektur menjadi sarana untuk mengintensifkan pemahaman tersebut. b) Memanfaatkan arsitektur dipahami sebagai tindakan untuk mendapatkan kebaikan dari arsitektur dan praktik yang terkait dengannya termasuk peraktik mewujudkan itu sendiri. Dengan memosisikan membangun sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan, maka ketidakpanggahan menjadi hal yang diperlukan agar bangunan dapat diwujudkan secara berulang terus menerus. c) Menghayati arsitektur didefiniskan sebagai cara untuk menginternalisasikan pengalaman sehingga menjadi pemahaman verbal, spasial, spiritual dan terutama praktikal yang diterapkan dalam penciptaan arsitektur. Menghayati arsitektur melalui penanganan komponen tak-panggah menjadikan praktik membangun sebagai sarana pembelajaran kultural yang sangat penting untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang mendasarinya. Ketidak-panggahan dalam arsitektur khususnya yang terwujud melalui pembangunan berulang dengan material tak-panggah di Kramat Buyut Trusmi memiliki aspek-aspek sebagai berikut: a) Pembaruan bangunan yang berulang secara berkala dalam skala yang besar yang menjadikan arsitektur sebagai wujud ciptaan baru sekaligus ciptaan lama. Dalam hal ini dualitas antara memperbarui bangunan dan kembali ke momen asali menjadi titik temu yang mendasar. Masyarakat memperlakukan bangunan sebagai sarana untuk mempertalikan kembali keberadaan mereka dangan momen asal-muasal tapi juga sekaligus mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. 239 b) Partisipasi masyarakat yang ekstensif menjadikan peleburan batas antara pembuat dan pengguna bangunan, antara tindakan mencipta dan memanfaatkan bangunan, serta antara daya cipta dan daya guna. Membangun tak lagi dipahami sebagai proses mempersiapkan konstruksi untuk dimanfaatkan kemudian, tetapi juga sebagai bentuk pemanfaatan. c) Motivasi spiritual dalam penciptaan dan pemanfaatan menjadikan keseluruhan proses tersebut dapat diintegrasikan sebagai upaya mendapatkan berkah dengan mengkontribusikan potensi yang dimiliki. Motivasi tersebut terungkap dalam proses membangun dengan pola keterlibatan masyarakat yang beragam dengan masyarakat berperan sebagai pendukung seperti pada saat Buka Sirap; masyarakat berperan sebagai pelaku utama seperti pada saat Memayu; dan bahkan masyarakat sebagai inisiator seperti pada sejumlah pemugaran. Dari kesemua ragam relasi tersebut bangunan dan proses membangun menjadi sarana pertukaran antara potensi yang dimiliki masyarakat dengan berkah yang bisa mereka peroleh. 7.3 Saran untuk Kajian Berikutnya Kramat Buyut Trusmi dan lingkungan sekitarnya masih relatif sedikit dikaji sementara kajian ini memiliki banyak keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam kajian-kajian berikutnya. Keterbatasan dan saran pengembangan tersebut antara lain adalah: a) Lingkup Objek. Kajian ini berfokus pada Kramat Buyut Trusmi. Bangunan-bangunan terkait yakni omah gede dan bele gede hanya sekilas disinggung dalam kaitannya dengan perkembangan awal di Desa Trusmi. Kelima bangunan “satelit” tersebut diyakini penduduk setempat sebagai hunian cikal bakal di masing-masing bagian Desa Trusmi. Dengan usia lebih dari 400 tahun, bangunan-bangunan tersebut dapat dispekulasikan sebagai salah satu dari rumah tertua di Jawa yang 240 berpotensi untuk menjadi jembatan evolusi rumah Jawa dari masa praIslam sebagaimana tergambarkan di relief-relief candi dan bangunan tradisional Jawa yang lazim kita jumpai sekarang ini. b) Lingkup Ranah Ilmu Arsitektur. Kajian ini menekankan pada pengembangan teori-teori dasar arsitektur. Kramat Buyut Trusmi sebagai fenomena yang kompleks dan khas potensial untuk mengembangkan berbagai ranah keilmuan arsitektur, antara lain: ranah sosial-ekonomi untuk memahami relasi antara Kramat dan pengusaha-pengusaha batik di Trusmi; ranah perilaku untuk memahami pola-pola perilaku yang melandasi ritus dan peziarahan di Kramat ini; ranah tipologi untuk memahami ragam bentuk bangunan di masa awal yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi tipe-tipe bangunan tradisional sebagaimana kita pahami sekarang ini; dan ranah teknologi bangunan untuk memhami kekuatan dan keandalan material dan komponen bangunan tak panggah tersebut. c) Lingkup Metoda Kajian. Kajian ini menggunakan metoda fenomenologi dan hermeneutika yang mengikis batas antara subjek dan objek kajian. Metoda lain yang potensial untuk dikembangkan berdasar karakeristik fifik tempat ini antara lain; metoda historis-arkeologis untuk merekonstruksi masa silam tempat ini; metoda perencanaan partisipatif dengan melakukan eksperimentasi sosial dengan masyarakat setempat guna merumuskan konsep pelestarian dan pengembangan Kramat Buyut Trusmi; serta metoda research for desgn dengan melakukan eksplorasi rancangan yang berbasis pada ke tak-panggahan dalam konteks arsitektur kontemporer. 241 Halaman ini dibiarkan kosong 242 REFERENSI Ballantyne, Andrew (2007) Deleuze and Guattari for Architects. Routledge: London. Bourdieu, Pierre (1990) The Logic of Practice, Stanford, CA: Stanford University Press. Braham, William W. et. al. eds. (2007) Rethinking Technology: A Reader In Architectural Theory. Routldedge: London. Cairns, Stephen (2006) “Notes for an alternative history of the primitive hut” dalam Jo Odgers, Flora Samuel dan Adam Sharr (eds.) Primitive: Original Matters in Architecture. Routledge: Oxon. Creswell, John W. (2007) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. London: SAGE Publication. Domenig, Gaudens (1980) Tektonik im Primitiven Dachbau. ETH Austellungkatalog Götterstitz. Domenig, Gaudens (2014) Religion and Architecture in Premodern Indonesia. Leiden: KITLV. Frampton, Kenneth (1995) Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge, MA: MIT Press. Frampton, Kenneth (2002) “Rappel a l’ordre: the case for the tectonic” dalam Alan Read (ed.) Architecturally Speaking Practices of Art, Architecture and the Everyday. London: Routledge. h. 177-197. 243 Gillespie, Susan (2007) "When is a House?" dalam R. Beck (ed.) The Durable House: House Society Models in Archaeology, Center for Archaeological Investigations Occasional Paper No. 35. Carbondale, IL h. 25-50. Habraken, N.J. (1998) The Structure of the Ordinary: Form and control in the Built Environment. Boston: MIT Press. Hale, Jonathan (2006) “Gottfried Semper’s primitive hut Duration, construction and self-creation”, dalam Jo Odgers, Flora Samuel dan Adam Sharr (eds.) Primitive: Original Matters in Architecture. New York: Routledge. Hale, Jonathan (2012) “Architecture, Technology and the Body: From the Prehuman to the Posthuman” dalam Greig Crysler, Stephen Cairns dan Hilde Heynen. The SAGE Handbook of Architectural Theory. London: SAGE Publications Ltd, h. 513-533. Hale, Jonathan (2013) "Critical Phenomenology: Architecture and Embodiment." Architecture & Ideas, Vol. XII, h. 18-37. Heidegger, Martin (2001a) “Building Dwelling Thinking” dalam Heidegger, M. Poetry, Language, Thought, New York, Harper and Row, h. 141-160. Heidegger, Martin (2001b) “The Thing” dalam Heidegger, M. Poetry, Language, Thought, New York, Harper and Row, h. 161-184. Heidegger, Martin (2001c) “Poetically Man Dwells” dalam Heidegger, M. Poetry, Language, Thought, New York, Harper and Row, h. 209-241. Holl, Steven (1989) Anchoring, New York, Princeton Architectural Press. Holl, Steven (1994a) “Questions of Perception, Phenomenology of Architecture” dalam Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez, A. (1994) Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, Tokyo, A + U Publ. Co, h. 40-42. 244 Holl, Steven (1994b) “Phenomenal Zones” dalam Holl, S., Pallasmaa, J. & PerezGomez, A. (1994) Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, Tokyo, A + U Publ. Co, h. 44-120. Holl, Steven (1994c) Archetypal Experiments of Architecture, dalam Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez, A. (1994) Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, Tokyo, A + U Publ. Co, h. 122-134. Hvattum, Mari (2004) Gottfried Semper and the Problem of Historicism. Cambridge: Cambridge University Press. Hvattum, Mari (2006) “Origins redefined: A tale of pigs and primitive huts” , dalam Jo Odgers, Flora Samuel dan Adam Sharr (eds.) Primitive: Original Matters in Architecture. New York: Routledge. Ingold, Tim (2013) Making: Anthropology, archaeology, art and architecture. Oxon, NY: Routledge. Jumsai, Sumet (dengan kontribusi Richard Buckminster Fuller) (1988) Naga: Cultural Origins in Siam and the West Pacific. Singapura: Oxford University Press Junyk, Ihor (2013) “‘Not Months But Moments’: Ephemerality, Monumentality and the Pavilion in Ruins”. Open Arts Journal. issue 2, h. 1-15. Klassen, Winand (1992) Architecture and Philosophy: Phenomenology, Hermeneutics, Deconstruction. Cebu, Universty of San Carlos Press. Kruft, Hanno-Walter (1994) A History of Architectural Theory: from Vitruvius to the present. London: Princeton Architectural Press. Kumar, Ann (2009) Globalizing the Prehistory of Japan: Language, genes and civilization. Oxon: Routledge. Kwanda, Timoticin (2012) “The Tradition of Architectural Conservation and the Intangible Authenticity: The Case of Ki Buyut Trusmi Complex in Cirebon, 245 Indonesia”. Desertasi tidak dipublikasikan pada National University of Singapore. Laugier, Marc A. (2004 [1753]) “Essai on Architecture”, dalam Liane Lefaivre dan Alexander Tzonis (ed.) The Emergence of Modern Architecture: A documentary history from 1000-1810. London: Routledge. h. 333-339. Leach, Neil (2001) “The Dark Side of the Domus” dalam Andrew Ballantyne (ed.), What is Architecture?, London: Routledge. Lin, Zhongjie (2010) Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan. London: Routledge. Milizia, Fransesco (2004 [1797]) “Dictionary of the Fine Arts of Design”, dalam Liane Lefaivre dan Alexander Tzonis (ed.) The Emergence of Modern Architecture: A documentary history from 1000-1810. London: Routledge. h. 459-466. Mitchell, Andrew J. (2015) The Fourfold: Reading the Late Heidegger. Evanston: Northwestern University Press. Moran, Demot (2000) Introduction to Phenomenology, London, New York, Routledge. Nistchke, Gunter (1979) “Shime: Binding/Unbinding”. Architectural Design 44, h. 747-791. Norberg-Schultz, Christian (1963) Intentions in Architecture, Oslo, Allen & Unwin LTD. Norberg-Schulz, Christian (1971) Existence, Space and Architecture, London, Studio Vista London. Norberg-Schulz, Christian (1979) “Kahn, Heidegger and the Language of Architecture. Oppositions, vol. 18, h. 29-47. 246 Norberg-Schulz, Christian (1980) Genius Loci, Towards a phenomenology of architecture, New York, Rizzoli. Norberg-Schulz, Christian (1985) The Concept of Dwelling, on the way to figurative architecture, New York, Rizzoli. Norberg-Schulz, Christian (2000) Architecture: Presence, Language, Place, Milan, Skira. Otero-Pailos, J. (2012) “Architectural Phenomenology and the Rise of the Postmodern” dalam Greig Crysler, Stephen Cairns dan Hilde Heynen. The SAGE Handbook of Architectural Theory. London: SAGE Publications Ltd, h. 136-151. Pallasmaa, Juhanni (1994) “An Architecture of the Seven Senses”. In: Holl, S., Pallasmaa, J. & Perez-Gomez, A. (1994) Questions of Perception, Phenomenology of Architecture, Tokyo, A + U Publ. Co, h. 33-49. Pallasmaa, Juhanni (1996) The Eyes Of The Skin, Architecture and the Senses, London, Academy Editions. Perez-Gomez, Alberto (1983) Architecture and the crisis of modern science, Cambridge, The MIT Press. Poerwadarminta, W.J.S. (1939) Baoesastra Djawa.Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers. Reid, Anthony (1992) Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450:1680, Jilid 1: Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ricoeur, Paul (1971) “The Model of the Text: Meaningful Action Considered as Text”. Social Research, vol 38, h. 529-555. Riegl, Alois, (1982) “The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin”, Oppositions 25, h. 21-56. 247 Robertson, Scott (2012) “Significant Pavilions: The Traditional Javanese House as a Symbolic Terrain”. Desertasi tidak dipublikasikan pada University of New South Wales. Robson, Stuart dan Singgih Wibisono (2002) Javanese-English Dictionary. Hongkong: Periplus. Sadler, Simon (2005) Archigram: Architecture without Architecture, MIT Press Seamon, David (2017) “A Phenomenological and Hermeneutic Reading of Rem Koolhaas’ Seattle Central Library: Buildings as lifeworlds and architectural texts” dalam Ruth Dalton dan Christoph Hölscher (ed.) Take One Building: Interdisciplinary Research Perspectives of the Seattle Central Library. Oxon: Routledge, h 132-167. Seamon, David (2000) “A Way of Seeing People and Place: Phenomenology in Environment-Behavior Research,” dalam S. Wapner, J. Demick, T. Yamamoto, dan H. Minami (ed.), Theoretical Perspectives in Environment‐Behavior Research. New York: Plenum, h. 157–178. Semper, Gottfried (1989 [1851]), “The Four elements of Architecture: A contribution to the study of architecture” dalam Gottfried Semper (diterjemahkan dan disunting oleh Harry Francis Mallgrave dan Wolfgang Herrmann) The Four Elements of Architecture and Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press, h. 74-129. Semper, Gottfried (2004 [1863]), Style in the Technical or Tectonic Arts: or, Practical Aesthetics (diterjemahkan oleh Harry Francis Mallgrave dan Michael Robinson) Los Angeles: Getty Research Institute. Shirazi, Muhammad R. (2009) “Architectural Theory and Practice, and the Question of Phenomenology (The Contribution of Tadao Ando to the Phenomenological Discourse)”. Disertasi tidak dipublikasikan pada Universitas Cottbus, Berlin. 248 Shirazi, Muhammad R. (2014) Towards an Articulated Phenomenological Interpretation of Architecture: Phenomenal Phenomenology. Oxon: Routledge. Vibaek, Kasper S. (2014) Architectural System Structures: Integrating design complexity in industrialized construction. London: Routledge. Vitruvius, Marcus P. (1914) The Ten Books on Architecture (diterjemahkan oleh Morris Hicky Morgan). London: Oxford University Press. Waterson, Roxana (1990) Living House: The Anthropology of Architecture in Southeast Asia. Singapura: Oxford University Press. West-Pavlov, Russell (2009) Space in Theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam: Rodopi. Winichakul, Thongchai (1997) Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Manoa: University of Hawaii. 249