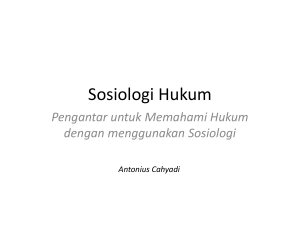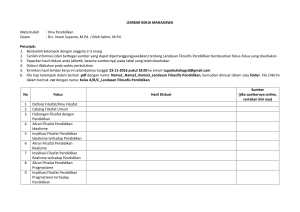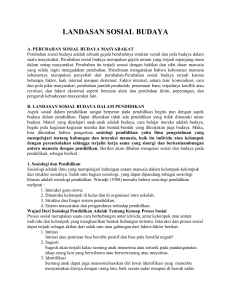sisi filosofis al-qur`an: beberapa kisah ilustratif
advertisement

Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) SISI FILOSOFIS AL-QUR’AN: BEBERAPA KISAH ILUSTRATIF Aris Widodo* Abstrak:Al-Qur’an merupakan buku-petunjuk yang mampu mengakomodasi berbagai level pemikiran manusia. Dengan gayabahasa yang khas, ia juga bisa ditilik dari berbagai bidang: hukum, kalam, filsafat, dan tasawuf, terkait dengan kecenderungan sang pentadabbur kitab-suci umat Islam ini. Oleh karena itu, al-Qur’an sebetulnya juga bisa dijadikan titik-berangkat untuk mata-kuliah filsafat, karena ia memberikan bahan yang melimpah bagi perenunganperenungan filosofis. Tulisan berikut memberikan ilustrasi bagaimana al-Qur’an dengan kisah-kisah yang disuguhkannya bisa menggugah sensitivitas filosofis kita. Sambil merujuk ke enam cabang filsafat, yaitu logika, epistemologi, kosmologi, metafisika, etika, dan estetika, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa al-Qur’an itu dalam aspek tertentu bisa kita klaim memiliki sisi-filosofis. Quran is a guide book that is able to accommodate many human beings’s thought levels. By special language style, it can also be viewed from various fields like law, theology, philosophy, and tasawuf related to reviewer’s preference. Therefore, Quran, in fact, can also be a starting point for philosophical study because it gives various materials to philosophical contemplations. This paper gives illustration of how the Quran with its stories in it is able to arouse our philosophical sensitivities. By referring to six branches of philosophy i.e. logic, epistemology, cosmology, metaphysic, ethic, and esthetic, this paper tries to show that the Quran in certain aspect can be claimed by us to have philosophical side. Kata kunci: Al-Qur’an, Filosofis, Cabang Filsafat *. Jurusan Syari’ah STAIN Parepare, Sulawesi Selatan 41 42 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 PENDAHULUAN Al-Qur’an merupakan manifestasi janji Tuhan yang secara implisit dikemukakan-Nya pada saat memberikan instruksi kepada Adam dan Hawa untuk “turun” dari taman-syurga. Dalam kesempatan itu, Tuhan menghantar kepergian Adam dan Hawa dengan sabda-Nya, “Turunlah kalian semua dari taman-syurga; ketika datang petunjuk kepada kalian, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku itu, niscaya dia akan terbebas dari perasaan-takut dan sedih” (QS. al-Baqarah: 38). Ayat ini memberi isyarat bahwa akan datang petunjuk Tuhan kepada Adam dan Hawa beserta keturunannya yang akan menjalani karir kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, bisa dipahami jika kemudian al-Qur’an (QS. al-Baqarah: 2) mengajukan klaim-diri sebagai kitab petunjuk (hudan). Dalam memberikan petunjuk kepada manusia, Tuhan menurunkan alQur’an dengan gaya-bahasa yang memungkinkan manusia, dengan berbagai latar-belakang disiplin dan tingkat intelektualnya, untuk memahami petunjuk di dalamnya. Tidak mengherankan jika kemudian para sarjana muslim mendapat bahan-baku yang melimpah untuk kajian di bidangnya masingmasing; para ahli hukum Islam, ahli kalam, ahli filsafat, dan ahli tasawuf merasa mendapat sumber untuk titik-tolak pengkajiannya, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat “dan apabila kalian berselisih-pendapat mengenai sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul-Nya” (QS. al-Nisa’: 59). Maka bermunculanlah beribu-ribu jilid buku di berbagai bidang pengkajian—tafsir ahkam, tafsir kalam, tafsir falsafi, dan tafsir shufi—yang semuanya bertolak dari ayat-ayat kitab-suci umat Islam ini. Tulisan berikut juga akan mengambilbagian dalam mengkaji salah satu bidang disiplin, yaitu filsafat, dengan merujuk ke dalam al-Qur’an sebagai titik tolaknya. Salah satu metode yang dipakai Tuhan untuk mengajari manusia adalah dengan menampilkan kisah-kisah, karena itu di dalam al-Qur’an banyak kisah dari orang-orang masa lalu; bahkan satu surat di dalam al-Qur’an, yaitu surat ke-28, diberi nama al-Qashash (kisah-kisah), karena dengan kisah-kisah tersebut manusia bisa bercermin dan mengambil pelajaran (‘ibrah) darinya. Dalam kaitannya dengan mata-kuliah filsafat, sebetulnya kita juga bisa menjumput kisah-kisah tersebut sebagai ilustrasi untuk bertolak ke perenunganperenungan filosofis. Satu ilustrasi berikut bisa dijadikan pendahuluan. Dalam surat al-An’am, ayat 76-79, al-Qur’an menuturkan perjalanan intelektual-spiritual Ibrahim ketika “mencari” Tuhan. Dikisahkan bahwa pada Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 43 saat Ibrahim melayangkan pandang ke arah langit di waktu malam, didapatinya kerlip bintang di sana, sehingga bergembiralah Ibrahim karena telah berhasil menemukan Tuhan, seraya berseru, “Inilah Tuhan-ku.” Namun, ketika bintang tersebut akhirnya “dikalahkan” oleh rembulan, per-hati-an Ibrahim pun terpikat oleh sang rembulan, sehingga kembali berseru, “Inilah Tuhan-ku.” Akan tetapi, ketika rembulan pun menjadi sirna saat muncul sang mentari, maka Ibrahim pun berketetapan, “Inilah Tuhan-ku, karena Yang Ini lebih besar.” Namun, sekali lagi, Ibrahim dikecewakan oleh fakta-empiris bahwa mentari pun dikalahkan oleh sang malam, sehingga akhirnya dia menyatakan perasaannya, “Sesungguhnya aku tidak suka yang ‘tenggelam’ (al-Afilîn).” Dengan pernyataannya tersebut, berarti Ibrahim telah mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mestilah bukan satu di antara lingkaran-setan faktaempiris “yang saling dikalahkan” ini: malam dikalahkan oleh munculnya bintang; bintang dikalahkan oleh rembulan; rembulan dikalahkan oleh matahari; dan matahari kembali dikalahkan oleh malam. Yang masih “tenggelam” atau “dikalahkan” oleh yang lain pastilah dikuasai oleh pihak yang “mengalahkan” tersebut, dan, dengan demikian, tidak layak dipandang sebagai Tu[h]an (:Tuan) yang sejati. Konsekwensi lanjutan dari pernyataannya itu juga berarti bahwa Ibrahim tengah bersiap-siap melanjutkan perjalanan mencari Tuhan dengan meninggalkan alam-fisik menuju alam-metafisik. Ilustrasi di atas memberi isyarat bahwa meskipun al-Qur’an bukanlah kitab-filsafat, namun pola penuturan al-Qur’an seringkali menunjukkan bahwa kitab ini dalam aspek tertentu bersifat filosofis, atau memuat karakteristik filsafat. Berbicara tentang karakteristik filsafat seringkali tidak mudah, mengingat istilah filsafat sendiri termasuk sebuah terma yang paling banyak didefinisikan; masing-masing filosof seakan memiliki hak untuk memberikan definisinya sendiri, sehingga banyak definisi bermunculan berkaitan dengan terma ini. Namun, dari sekian banyak definisi yang diberikan, misalnya ada beberapa istilah yang pasti tidak ketinggalan ketika filsafat didefinisikan, yaitu: radikal, kritis, komprehensif, sistematis, dan koheren (Tim Penulis Rosda, 1995: 249-250). Dengan demikian, karakteristik filsafat yang penulis maksud di sini adalah: radikal, kritis, komprehensif, sistematis, dan koheren; dan yang dimaksud “sisi-filosofis al-Qur’an” dalam hal ini adalah sisi radikal, kritis, komprehensif, sistematis, dan koheren dari al-Qur’an dalam bertutur mengenai suatu objek-permasalahan. 44 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 Setelah satu ilustrasi pendahuluan di atas, dalam Pembahasan berikut penulis akan menyuguhkan lebih lanjut beberapa kisah yang bisa dijadikan ilustrasi mengenai sisi-filosofis al-Qur’an. Dalam tulisan ini, penulis akan membagi ilustrasi mengenai sisi filosofis al-Qur’an ke dalam enam cabang tradisional filsafat, yaitu: logika, epistemologi, kosmologi, metafisika, etika dan estetika. Namun, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam pembahasan mengenai sisi-filosofis al-Qur’an, ada informasi menarik lainnya dalam alQur’an dalam kaitannya dengan karakteristik filsafat. Bila kita merujuk surat Ibrahim, ayat 24-26, di situ kita akan mendapati sebuah parabel yang menarik, “...perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik: akarnya teguh dan cabangnya [menjulang] ke langit; pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya... Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk: akar-akarnya telah tercerabut dari bumi, sehingga tidak dapat tetap [tegak] sedikitpun.” Ayat di atas memberi ilustrasi bagaimana sebuah tatanan “kalimat” yang baik, yaitu: akarnya menghunjam-kuat ke tanah, sementara cabangnya menjulang ke langit, dan pohon tersebut menghasilkan buah. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit istilah filsafat tidak disebut dalam al-Qur’an, namun kita bisa menjumput beberapa unsur yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan filsafat. Karakterikstik radikal dan kritis dari filsafat bisa diisyaratkan oleh terma “akarnya menghunjam-kuat ke tanah” mengingat istilah radikal, dari bahasa latin radix, berarti “akar”, di mana akar tersebut secara selektif menyerap berbagai bahan-makanan di dalam tanah yang berguna bagi “tubuh”nya; karakteristik komprehensif digambarkan oleh frase “cabangnya menjulang ke langit” yang berarti meliputi berbagai aspek; sistematis dan koheren digambarkan oleh istilah “memberikan buah,” karena koheren maksudnya adalah tidak-saling bertentangan, dan pohon yang baik manakala semuanya, mulai dari akar, batang, cabang, ranting, dan buah, saling bersinergi sebagai sebuah entitas yang sistematis dan tidak saling menegasikan. Penulis telah memaparkan beberapa karakteristik filsafat yang dimaksud. Selanjutnya, bagian berikut akan memberikan gambaran lebih jauh mengenai sisi-filosofis al-Qur’an dengan merujuk ke enam cabang filsafat: logika, epistemologi, kosmologi, metafisika, etika, dan estetika. Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 45 PEMBAHASAN A. Logika dalam al-Qur’an: Dimensi Praktis Logika merupakan cabang filsafat yang mencoba menggariskan peraturan-peraturan yang bisa menuntun subjek yang berfikir ke arah pemikiran yang benar (Titus, 1984: 25). Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornby, 1995: 1241), berfikir (to think), didefinisikan, salah satunya, sebagai “to direct one’s thought to a certain subject” (mengarahkan pikiran ke suatu pokok-permasalahan tertentu). Jika kita sedang berfikir tentang Tuhan, misalnya, berarti kita sedang mengarahkan pikiran kita ke pokokpermasalahan tersebut, yaitu Tuhan. Logika, dalam hal ini, memberikan koridor agar pemikiran kita tentang pokok-permasalahan tersebut tidak mengalami sesat-fikir (fallacy). Secara teoretis, al-Qur’an memang tidak membicarakan logika; namun secara praksis, al-Qur’an telah banyak menerapkan prinsip-prinsip logika dalam berbagai pokok-permasalahan, misalnya ketika berbicara tentang Tuhan. Ketika membawa perenungan tentang Tuhan, kitab-suci umat Islam ini tidak memberikan definisi secara langsung apa itu Tuhan. Yang diberikan al-Qur’an adalah menggambarkan beberapa karakteristik berkenaan dengan-Nya. Melanjutkan ilustrasi awal dalam Pendahuluan mengenai pencarian Ibrahim tentang Tuhan, meskipun di situ tidak secara eksplisit disebutkan karakteristik Tuhan, namun kita bisa menarik inferensi tentang “Apa” atau “Siapa” yang layak disebut sebagai Tuhan ketika Ibrahim menyatakan, “Aku tidak suka yang tenggelam.” Dengan pernyataannya ini, berarti al-Qur’an, melalui penuturan Ibrahim, memberikan karakteristik tentang Tuhan, bahwa Tuhan bukanlah “yang tenggelam” atau “yang dikalahkan,” melainkan kebalikannya: “Yang Maha Kuasa.” Melalui penuturan Ibrahim pula bisa kita nyatakan bahwa Yang Maha Kuasa, menurut al-Qur’an, bukan salah satu di antara faktaempiris, karena yang bersifat empiris ini masih masuk dalam lingkaran-setan yang dikuasai oleh yang lain. Selanjutnya, tentu muncul pertanyaan, “Kalau demikian, siapakah yang dimaksud dengan Yang Maha Kuasa itu?” Untuk menjawab pertanyaan di atas, menarik untuk melanjutkan kisah lain tentang Ibrahim dalam kaitannya dengan karakteristik Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa, yang tertera dalam surat al-Baqarah: 258. Ketika Ibrahim didebat oleh Namrudz, Raja Babilonia, tentang siapakah Tuhannya, Ibrahim menjawab bahwa Tuhannya adalah “yang kuasa menghidupkan dan mematikan.” Kemudian Namrudz menimpali bahwa dia pun memiliki kuasa untuk 46 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 menghidupkan (membiarkan hidup) dan mematikan (menghukum mati), sehingga Namrudz pun berhak menyandang predikat sebagai Tuhan. Maka, Ibrahim melanjutkan proposisinya, “Sesungguhnya Tuhan memiliki kuasa menerbitkan matahari dari timur,” kata Ibrahim, “maka terbitkanlah matahari itu dari barat.” Dengan kalimat-kritis yang bernada permintaan sekaligus penyangkalan ini sang Namrudz pun terdiam-seribu-bahasa (buhita). Dengan demikian, klaim Namrudz mengenai ketuhanannya pun runtuh, karena klaimnya lebih luas dari pembuktiannya: tidak mampu membuktikan sisi ke-kuasa-annya terhadap peredaran benda-benda semesta-angkasa. Ibrahim termasuk Nabi yang sering dikisahkan berdebat tentang ketuhanan dengan ketajaman logika. Permainan cantik logika kembali dipraktekkan Ibrahim dengan “menghabisi” patung-patung yang dijadikan sesembahan kaumnya, dan menyisakan patung yang terbesar. Ketika kaumnya menuduhnya telah melakukan perbuatan tersebut, maka Ibrahim pun dengan cerdik mengarahkan telunjuk ke patung yang terbesar dan memposisikannya sebagai pihak tertuduh. Ketika kaumnya menyatakan bahwa tidak mungkinlah patung terbesar itu yang melakukan pengrusakan patung-patung lainnya, Ibrahim pun melontarkan pertanyaan yang menggugat koherensi pola-pikir dan tindakan kaumnya, “lalu bagaimana kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak kuasa memberi manfaat dan mendatangkan madharat kepada kalian?” (QS. al-Anbiya’: 62-66). Meskipun Namrudz dan rakyatnya jelas dikalahkan oleh Ibrahim dengan jalan kekuatan logika, namun dengan “logika kekuatan” yang dimilikinya, Namrudz tetap memerintahkan agar Ibrahim diberi hukuman, yaitu dilemparkan ke api-unggun. Pada titik ini, Ibrahim mengeluarkan pertanyaan yang lagi-lagi mengundang penalaran logis: manakah yang lebih aman, berlindung kepada “Sesuatu” yang memiliki kuasa berbuat sesuatu, ataukah berlindung kepada “sesuatu” yang tidak kuasa berbuat sesuatu apa pun? (QS. al-An’am: 81). Pertanyaan yang sangat logis ini tetap tidak menyentuh kesadaran mereka, bahkan menyulut mereka untuk berseru, “Bakarlah dia dan bantulah Tuhantuhan kalian...” (QS. al-Anbiya’: 68). Kemudian terbuktilah proposisi Ibrahim ketika kemudian “Sesuatu” yang diyakininya kuasa berbuat sesuatu itu turun-tangan dan menyelamatkan Ibrahim dengan Sabda-Nya, “Wahai api, jadilah engkau dingin, dan keselamatan atas Ibrahim” (QS. alAnbiya’: 69). Dari sini, semakin lengkaplah keyakinan Ibrahim bahwa “Yang Maha Kuasa” itu bukanlah yang masuk dalam daftar fakta-empiris-terlihat, Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 47 melainkan “Sesuatu” di seberang fisik, “Sesuatu” yang, di kali lain, pernah dimintanya untuk memperlihatkan kuasa bagaimana menghidupkan yang mati (QS. al-Baqarah: 260). Dari berbagai fragmen kehidupan Ibrahim, jelaslah perjalanannya dalam mencari Tuhan melalui proses penalaran logis: dimulai dari pengamatan terhadap fakta-empiris, sampai kepada kesimpulan bahwa yang layak menyandang predikat sebagai “Tuhan” bukanlah salah satu di antara fakta-empiris tersebut, melainkan “Sesuatu” di seberang fisik yang, meskipun tak-terlihat, memiliki kuasa terbesar atas fakta-empiris. B. Al-Qur’an dan Kajian Epistemologi Epistemologi merupakan “cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki” (Hardono Hadi, 1994: 5). Di antara kajian epistemologi yang menyibukkan para filosof adalah: apakah sebetulnya pengetahuan itu; apa yang menjadi sumber pengetahuan; bagaimana validitas berbagai pengetahuan; bagaimana status-ontologis objek pengetahuan; bagaimana nilai sebuah pengetahuan; dan apakah terdapat hierarki pengetahuan. Dalam kaitannya dengan epistemologi, al-Qur’an banyak menyodorkan bahan-baku yang bisa menjadi titik-tolak perenungan filosofis. Bahan-baku yang disodorkan tersebut di antaranya diilustrasikan melalui kisah-kisah berikut. Mengenai “sumber pengetahuan,” misalnya, al-Qur’an menyodorkan kisah tentang Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman. Dalam surat an-Naml: 44, dikisahkan bahwa ketika Ratu Balqis diajak masuk oleh Nabi Sulaiman ke dalam istananya, maka tiba-tiba sang ratu menyingkapkan kain yang menutupi betisnya. Hal ini dilakukannya karena dalam pandangannya, lantai-istana (sharkh) yang sebetulnya terbuat dari kaca (qawarir) tersebut, terlihat seolaholah kolam-air yang besar (lujjah). Jika kita mengajarkan filsafat kepada mahasiswa Islam, kisah ini bisa kita jadikan ilustrasi mengenai perdebatan filosofis antara penganut skeptisisme di satu sisi, dan penganut empirisisme di sisi lain, bahkan juga penganut rasionalisme. Kisah ini bisa menjadi argumen penguat bagi penganut aliran skeptisisme bahwa “tidak ada sesuatu pun” (K. Bertens, 1994: 74) mengingat apa yang kita cerap dengan indera ternyata menipu, sama halnya dengan fenomena 48 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 fatamorgana yang menipu pandangan, seperti disebutkan dalam al-Qur’an, “seperti fatamorgana di dataran rendah yang disangka oleh orang yang kehausan sebagai air, namun ketika didatangi tempat tersebut ternyata tidak didapatinya air tersebut” (QS. an-Nur: 39). Kisah ini juga bisa dijadikan ilustrasi mengenai hantaman aliran rasionalisme terhadap empirisisme, bahwa seringkali indera itu menipu, sebagaimana banyak hal lain yang menunjukkan bahwa indera itu menipu, dan dengan demikian tidak bisa diandalkan sebagai sumber pengetahuan yang valid. Namun, kisah ini pun bisa dijadikan argumen penguat bagi penganut aliran empirisisme, dengan argumentasi bahwa: kita bisa mengenali penipuan indera juga dengan indera; sehingga dengan demikian, indera tidak selamanya menipu. Dengan satu kisah yang bisa dijadikan landasan-pijak awal bagi, minimal, ketiga aliran filsafat tersebut, kita selanjutnya bisa masuk ke perdebatan-filosofis para filosof berkaitan dengan sumber pengetahuan. Mengenai hierarki pengetahuan, kita bisa mencomot kisah perjalanan Musa dalam mencari ilmu. Dalam surat al-Kahfi: 60-82 diceritakan mengenai kisah Musa yang berguru kepada “hamba Allah” yang diberi ‘ilmu ladunniy. Di dalam kisah ini, dituturkan bahwa sang hamba Allah, yang sering disebut sebagai Khidr, melakukan beberapa tindakan “aneh”, yaitu melubangi perahu, membunuh pemuda, dan menegakkan dinding-rumah yang hampir roboh. Tindakan aneh tersebut tentu membuat Musa yang mengikutinya mengalami kebingungan. Kebingungan ini disebabkan oleh karena pengetahuannya yang masih sangat terbatas. Pada saat Khidr sudah memberikan penjelasan (ta’wîl) mengenai motif di belakang perilakunya yang aneh tersebut, barulah kebingungan Musa terobati karena sudah bisa memahaminya. Kisah ini bisa dijadikan sebagai ilustrasi mengenai pengetahuan yang bersifat hierarkis, bertingkat-tingkat. Kisah yang berkaitan dengan hierarki pengetahuan bisa juga diambil dari dialog antara Tuhan dan malaikat berkenaan dengan rencana menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pada saat malaikat merasa “aneh” dengan akan dijadikannya makhluk yang “merusak dan menumpahkan darah” sebagai khalifah, Tuhan pun melakukan ujian atas pengetahuan malaikat, yang kemudian menggiring kepada kesadaran bahwa pengetahuan mereka sangat terbatas (QS. al-Baqarah: 30-33). Berkaitan dengan “nilai pengetahuan” muncul perdebatan di kalangan filosof mengenai masalah apakah sebetulnya pengetahuan itu memiliki nilai. Secara garis besar, mereka terbelah ke dalam dua kelompok: satu kelompok Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 49 mempercayai value-neutral dari pengetahuan, bahwa pengetahuan itu bebasnilai; dan satu kelompok lainnya mempercayai sisi value-added dari pengetahuan, bahwa pengetahuan mestilah memiliki muatan-nilai. Untuk mengantar pembahasan kepada pokok-permasalahan filosofis ini, kita, sekali lagi, bisa merujuk kepada kisah ratu Balqis di atas, bagaimana pengetahuan yang keliru (“menganggap lantai istana sebagai kolam-air”) bisa menggiring kepada perilaku yang keliru pula (“menyingkap kain yang menutupi betisnya”). Untuk memperkaya ilustrasi ini, kita bisa mengambil kisah lain dalam al-Qur’an, surat al-Baqarah: 102, yang menceritakan kisah malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sebuah pengetahuan yang bisa “memisahkan pasangan hidup: suami-istri”. Dari sini, kita bisa beranjak kepada pembahasan mengenai permasalahan apakah sebetulnya pengetahuan itu bebas-nilai ataukah bermuatan nilai. C. Kajian Kosmologi Kosmologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakekat alamsemesta: bagaimana asal-usulnya; apa yang menjadi bahan-dasarnya (arche); bagaimana strukturnya sehingga bisa tertib-teratur (kosmos) seperti sekarang; apakah bersifat statis ataukah berkembang; apakah akan mengalami kehancuran; dan apakah akan mengalami penciptaan-ulang sesudah kehancurannya. Berkaitan dengan kosmologi ini, al-Qur’an banyak menyodorkan proposisi-proposisi yang bersifat saintifik. Mengenai masalah bagaimana alam semesta ini “lahir” misalnya, al-Qur’an memberikan statement, “Tidakkah orang-orang yang ingkar itu melihat bahwa langit dan bumi itu pada awalnya satu-padu, kemudian kami pisahkan keduanya” (QS. al-Anbiya’: 30). Ayat ini bisa kita jadikan titik-tolak perenungan filosofis mengenai apakah sebetulnya alam semesta itu qadim (azali) ataukah hadits (baru), yang sering diperdebatkan para filosof Muslim itu; juga mengenai apakah alam-semesta itu diciptakan dari sesuatu bahan, ataukah tidak (creatio ex nihilo). Sedangkan masalah apakah alam semesta itu bersifat statis ataukah mengembang (expanding) al-Qur’an menyodorkan terma mûsi’ûn/kami meluaskannya (QS. al-Dzariyat: 47). Apakah terma tersebut bisa dijadikan sandaran argumentasi bahwa alam-semesta itu mengembang? Di sinilah interpretasi atas ayat ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan persoalan saintifik-filosofis. 50 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 Kemudian, entah mengembang atau statis, persoalan lainnya adalah apakah alam-semesta yang “lahir” tersebut juga akan mengalami “kematian” (:kehancuran)? Al-Qur’an banyak sekali menyinggung persoalan ini dalam kaitannya dengan akan terjadinya kiamat. Namun, kita bisa membawa ayatayat itu ke “mahkamah” penalaran rasional: apakah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan logika-filosofis, ataukah tidak. D. Bidang Metafisika Metafisika merupakan cabang filsafat yang bergelut dengan permasalahan di seberang fisik, dan mencoba untuk merangsak-masuk lebih dalam lagi ke alam di balik realitas fisik dengan “membicarakan watak-watak yang sesungguhnya (ultimate) dari benda-benda atau realitas-realitas yang berada di belakang pengalaman langsung” (Harold H. Titus, dkk., 1984: 25). Selain kisah kisah pencarian Tuhan yang dilakukan Ibrahim yang mengarah ke alam di seberang fisik, kisah mengenai Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman di muka sebetulnya juga bisa kita pakai sebagai titik-berangkat untuk perenungan metafisis: kalau panca-indera bisa menipu dengan adanya halusinasi, maka apakah tidak demikian halnya dengan akal kita: apakah kita tidak tertipu oleh akal kita sendiri, dan menganggap sesuatu itu nyata-ada padahal sebetulnya tidak nyata-ada? Dari sini kita bisa masuk ke perenunganperenungan, misalnya, yang dilakukan oleh al-Ghazali dan Rene Descartes mengenai keraguan-metodis. Dengan pernyataan Rene Descartes “cogito ergo sum”-nya (Aku berfikir maka aku ada), selanjutnya kita bisa membahas apakah sebetulnya yang nyatanyata ada itu: apakah bersifat materi atau bersifat idea? Dari pintu-pembahasan ini, kita bisa menyinggung surat al-A’raf: 172 untuk masuk dalam perenungan Plato tentang Realitas yang Kekal dan alam yang berubah, yang merupakan sintesa dari dua filosof sebelumnya, Parmenides yang bersikukuh bahwa semesta sepenuhnya kekal tidak berubah (what is, is) dan Herakleitos yang meyakini bahwa semesta setiap waktu mengalami perubahan sebagaimana, you cannot step twice in the same river (setiap kali kita menyeberangi sungai yang sama, maka airnya tidak sama; segalanya mengalir/panta rhei) (Bertens, 1994: 43-48). Jika metafisika dimaknai dengan realitas di balik alam-fisik, maka alQur’an sebetulnya banyak sekali menyinggung persoalan ini, mengingat obyek Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 51 utama yang disodorkan al-Qur’an untuk dipercayai—Tuhan, malaikat, eskatologi—masuk dalam lingkup ini; bahkan al-Qur’an sendiri pada awalnya melalui proses metafisis, seperti diisyaratkan Tuhan dalam sabda-Nya, “Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas sehingga mereka bisa memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang yang ingkar itu akan berkata, ‘Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata,’” (QS. al-An’am: 7). Objek-objek yang disodorkan al-Qur’an ini, karena bersifat di seberang fisik (meta-fisis) bisa kita jadikan objek perenungan filosofis, apakah bisa dipertahankan secara rasional ataukah tidak. E. Kajian Etika Etika merupakan cabang filsafat yang mendiskusikan apakah hakekat hidup itu, dan bagaimana menjalani sebuah hidup yang bermakna. Etika “merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia (Frans Magnis-Suseno, 1997: 5). Dengan demikian, etika mencoba merumuskan pola agar kehidupan manusia tidak “seperti binatang-ternak, atau bahkan lebih parah dari itu” (QS. al-A’raf: 179). Salah satu persoalan utama dalam etika adalah apa yang sesungguhnya menggerakkan manusia untuk melakukan aktivitas; apa motivasi dasar mereka, dan apa yang mereka kejar? Untuk memulai pembahasan filosofis mengenai persoalan ini, kita bisa menjumput beberapa ilustrasi al-Qur’an mengenai karakteristik orang munafik dan orang beriman dalam melakukan suatu aktivitas, misalnya dalam hal melaksanakan shalat: mengapa orang munafik “berdiri dengan malas” (QS. al-Nisa’: 142) sementara orang beriman melakukan shalat dengan penuh kekhusu’an (QS. al-Mu’minun: 2). Mengapa orang dengan karakteristik berbeda menanggapi secara berbeda pula suatu aktivitas? Dari ilustrasi ini, kita selanjutnya mencoba membahas alternatifalternatif yang diajukan oleh, misalnya, Epikuros, Stoa, Aristoteles, Plato, Immanuel Kant, dan tokoh-tokoh etika lainnya berkaitan dengan apa yang mendorong dan dikejar oleh manusia dalam berbagai aktivitasnya, dan bagaimana yang ideal menurut para tokoh tersebut. F. Estetika Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas hakekat keindahan, dengan merujuk kepada beberapa pembahasan, seperti: apa sebetulnya indah 52 RELIGIA Vol. 13, No. 1, April 2010. Hlm. 41-54 itu; bagian mana dari kita dan objek yang kita cerap yang membuat kita menyebutnya indah; adakah perbedaan antara perasaan estetis dan perasaan lainnya (Tim Penulis Rosda, 1995: 5). Dalam kaitannya dengan estetika, al-Qur’an memberikan beberapa ilustrasi berupa kisah dan proposisi afirmatif. Kisah yang sangat menarik dalam al-Qur’an dalam kaitannya dengan nilai estetis adalah tentang Zulaikha beserta komunitas kaum hawa-nya, dan Yusuf. Seperti diceritakan dalam surat Yusuf: 23-32 bahwa Zulaikha “terperangkap” oleh pesona keindahan yang mewujud dalam diri Yusuf, sehingga berupaya untuk merayunya agar Zulaikha bisa merasakan keindahan itu; meskipun kemudian rayuan Zulaikha itu ditolak oleh Yusuf. Ketika komunitas kaum hawa mendengar isu Zulaikha dan Yusuf tersebut, mereka pun membuat gosip yang memerahkan telinga Zulaikha, sehingga memaksa Zulaikha untuk mendesain strategi agar komunitasnya tersebut tidak mencemoohnya. Caranya adalah memberi mereka pisau untuk mengiris hidangan, dan kemudian menghadirkan Yusuf di “cat-walk” agar mereka melihatnya. Maka, tatkala kaum hawa tersebut melihat keindahan yang terpancar pada diri Yusuf, mereka pun lupa-diri dalam arti harfiahnya: mereka melukai tangan sendiri tanpa sadar demi melihat Yusuf. Ini adalah salah satu perasaan yang terserap oleh objek keindahan, dan dari sini kita bisa bertolak untuk membahas persoalan filosofis apa sebetulnya keindahan itu, dan di manakah sebetulnya nilai keindahan itu ada. Filosof Jerman, Immanuel Kant, pernah berujar, “Dua hal memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub dan takzim yang senantiasa baru dan semakin bertambah, dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan-diri berkali-kali dan tanpa henti: langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam batinku.” (Tjahjadi, 1997: 5). Entah filosof ini pernah membaca al-Qur’an ataukah tidak, ayat al-Qur’an berikut menyodorkan fenomena alam sebagai objek keindahan, “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis; tidak akan engkau lihat ketidakseimbangan dalam ciptaan-Nya—maka ulangilah pandanganmu, adakah engkau temukan cacat?; kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi, niscaya tetap tidak akan engkau temukan cacat sampai pandanganmu sendiri menjadi letih. Dan langit-dunia telah Kami hiasi dengan bintang-bintang...” (QS. al-Mulk: 3-5). Ayat ini bisa juga kita jadikan sebagai ilustrasi untuk memulai perenungan tentang keindahan. Sisi Filosofis Al-Qur’an (Aris Widodo) 53 PENUTUP Al-Qur’an merupakan kitab-samawi yang mampu mengakomodasi berbagai level pemikiran manusia. Sebagaimana ia bisa dipahami oleh orang yang tingkat intelektualitasnya rata-rata, al-Qur’an juga bisa dianalisa oleh orang dengan tingkat intelektualitas tinggi, tentu dengan hasil ketajaman analisa yang berbeda. Begitu juga, al-Qur’an bisa ditilik dari sudut hukum, kalam, filsafat, dan tasawuf, terkait dengan kecenderungan sang pen-tadabbur kitabsuci umat Islam ini. Maka jika kita mengkaitkan al-Qur’an dengan matakuliah filsafat, sebetulnya kitab ini memberikan bahan yang melimpah bagi perenungan-perenungan filosofis. Tulisan ini memberikan ilustrasi bagaimana al-Qur’an dengan kisah-kisah yang disuguhkannya bisa menggugah sensitivitas filosofis kita. Sambil merujuk ke enam cabang filsafat, yaitu logika, epistemologi, kosmologi, metafisika, etika, dan estetika, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa al-Qur’an itu dalam aspek tertentu bisa kita klaim memiliki sisi-filosofis. Dengan demikian, ketika mengampu mata-kuliah filsafat kita bisa “sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui”: di satu sisi mengajak mahasiswa men-tadabbur-i al-Qur’an, dan di sisi lain membawa anak-didik ke perenungan filosofis. DAFTAR PUSTAKA Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1994 Gallagher, Kenneth T., Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, terj. Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 1994 Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 1995 Magnis-Suseno, Franz, 13 Tokoh Etika sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19, Yogyakarta: Kanisius, 1997 Musa, Faydh Allah ibn, Fat% al-Ra%mân li-þâlibi âyâti al-Qur’ân, Indonesia: Maktaba al-Dahlan (t.t.). Tim Penulis Rosda, Kamus Filsafat, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995 Titus, Harold H. dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984 Tjahjadi, S. P. Lili, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Yogyakarta: Kanisius, 1997