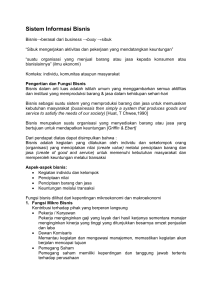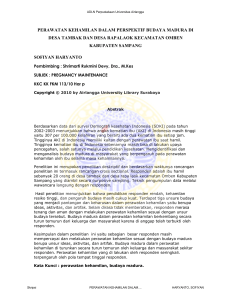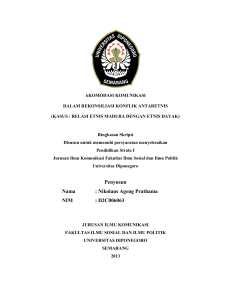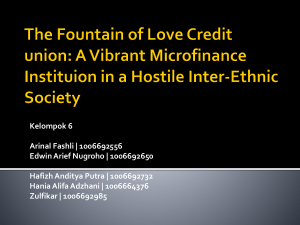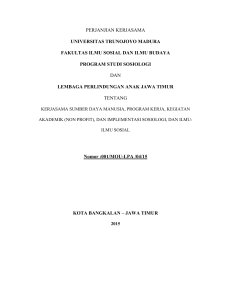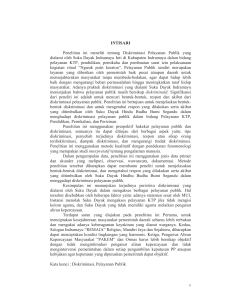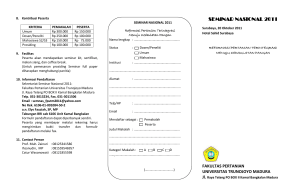1 Bab I Pendahuluan A. Dasar Pemikiran
advertisement

Bab I Pendahuluan A. Dasar Pemikiran Pembangunan jemaat adalah upaya teologi praktika untuk melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, dan memberikan masukan-masukan pelayanan secara utuh dan benar. Karena itu, pembangunan jemaat harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam gereja maupun di masyarakat. Dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi, gereja tentunya juga harus menyadari orientasi panggilannya dalam konteks konkret. Rob van Kessel menegaskan, dalam rangka gereja menempatkan diri, dan ditempatkan dalam dunia, pembangunan jemaat hadir di tengah-tengah tata ruang (fakta yang ada dalam dunia: struktur, relasi antar individu-kelompok-etnis yang berbeda, hukum dan sebagainya) dan waktu (siklus dan proses waktu yang selalu berubah) yang ada.1 Pembangunan jemaat dituntut mampu membawa perubahan positif bagi umat manusia dalam tata ruang dan waktu yang terus berubah. Dalam konteks itu, maka pembangunan jemaat bukan hanya sekadar memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteksnya, tetapi juga menyadari bahwa perubahanperubahan juga bisa dikendalikan sesuai dengan apa yang dikehendaki.2 Berdasarkan hal ini, pembangunan jemaat mengarahkan gereja secara teologis menjadi gereja yang vital, yaitu gereja yang menghayati keberadaan Allah dan imannya dalam konteks konkret. Untuk itu gereja yang vital, bukan hanya mengupayakan partisipasi warga jemaat dalam bergereja,3 tetapi juga partisipasi dengan segala totalitas hidup dalam relasinya dengan 1 Rob Van Kessel, 6 Tempayan Air: Pokok-pokok Pembangunan Jemaat, (Yogyakarta, Kanisius, 1997), 12 - 14. Haselaar, Paroki 2000: Bahan Studi Pembangunan Jemaat, (Yogyakarta, Kanisius, 2000), 17. 3 Jan Hendriks, Jemaat Yang Vital dan Menarik, (Yogyakarta, Kanisius, 2002), 28. 2 1 masyarakat sekitarnya.4 Rob van Kessel,5 menghubungkan vitalitas gereja dalam pembangunan jemaat, terkait dengan sejauh mana Injil relevan, bermakna, dalam penampilan serta penghayatan anggota jemaat di ranah praksis, berupa relasi antar sesama warga jemaat maupun relasi dengan masyarakat sekitarnya. Hooijdonk,6 mengatakan fungsi dasar setiap warga jemaat yang hidup di tempat tinggalnya (tata ruang dan waktu tertentu) adalah menampak relasi yang dikehendaki Allah yaitu hubungan pergaulan yang ditandai dengan nilai-nilai perdamaian (saling memaafkan, mengasihi). Relasi yang dikehendaki Allah tersebut, berlaku bagi semua manusia, tidak hanya antar sesama anggota jemaat saja.7 Dengan menekankan relasi positif dengan semua manusia, diharapkan nilai-nilai perdamaian, dapat dinampakkan dalam relasi antar sesama manusia secara benar.8 Itu berarti kehadiran pembangunan jemaat bukan hanya bagi dirinya sendiri (eksklusif-ritual-rutinitas), melainkan juga memberi manfaat bagi hubungan pergaulan umat di masyarakat.9 Dengan demikian nilai-nilai perdamaian dalam jemaat, terpancar melalui sikap dan tindakan umat dalam relasi sosialnya di masyarakat.10 Berangkat dari hal di atas, mengupayakan relasi yang positif menjadi unsur penting dalam pembangunan jemaat, sebab umat tidak terpisahkan dari pergaulannya dengan masyarakat.11 Itu berarti pembangunan jemaat berhadapan langsung dengan kenyataan konkret dalam masyarakat, seperti relasi antar masyarakat yang majemuk baik suku, agama dan 4 Bdk., Gilarso, Kamulah Garam Dunia: Tugas Umat Allah Dalam Masyarakat, Bagian Pertama (Yogyakarta, Kanisius, 2003), 9. 5 Bdk., Rob van Kessel , 6 Tempayan Air, 7. 6 Hooijdonk, Batu-Batu yang Hidup, Pengantar ke dalam Pembangunan Jemaat, (Yogyakarta, Kanisius, 1996), 143. bdk., Rob van Kessel, 6 Tempayan Air, 7. 7 Gilarso, Kamulah Garam Dunia: Tugas Umat Allah dalam Masyarakat, Bagian Kedua, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), 33. 8 Hooijdonk, Batu-batu yang Hidup, 13, 141-142. 9 Gerben Heitink, Teologi Praktis, Pastoral dalam Era Modernitas-Postmodernitas, (Yogyakarta, Kanisius, 1999), 25. 10 Bdk., Gerrit Singgih, Berteologi Dalam Konteks, (Jakarta, BPK Gunung Mulia & Kanisus, 2000), 225. 11 Bdk., Gilarso, Kamulah Garam Dunia, Bagian kedua, 35. 2 budaya. Bahkan Jan Hendriks menilai,12 sebagai pintu masuk mewujudkan partisipasi warga jemaat sangat terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada dalam masyarakat, termasuk pluralisme suku dan kultural. Menurut Hendriks,13 proses-proses konflik negatif akan terjadi apabila jemaat tidak bisa memahami pluralitas secara positif. Dampaknya, berkurangnya relasi positif baik antar sesama anggota jemaat, maupun dengan masyarakat sekitarnya. Itu berarti membangun relasi positif sebagai bagian dari teologi praktika untuk merefleksikan dimensi relasi warga jemaat baik dalam gereja maupun di masyarakat menjadi penting.14 Dengan demikian membangun relasi positif antar sesama manusia, sekaligus membantu pengharapan pada masyarakat tidak terpisahkan dari setiap upaya pembangunan jemaat. Konsep ini akan menjadi acuan dalam pembangunan jemaat yang kontekstual. Berkaitan dengan konteks pembangunan jemaat yang dihadapi GKE Sampit yaitu rusaknya relasi antara etnis Dayak dan etnis Madura yang menjadi masalah tesis ini, maka keterbukaan pembangunan jemaat terhadap teori sosial lainnya menjadi penting. B. Latar Belakang Masalah dan Topik Relasi antara etnis Dayak dan Madura, baik di Kalimantan Barat (Kalbar) maupun di Kalimantan Tengah (Kalteng) tak dapat dipungkiri telah menjadi masalah kemanusiaan yang fenomenal. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengalaman konflik antar kedua etnis yang sering muncul tenggelam. Dalam catatan sejarah konflik kedua etnis misalnya di Kalbar tercatat ada 12 kali konflik antara etnis Dayak dan Madura, tahun 1952, 1967, 1968, 1976, 12 Jan Hendriks, Jemaat Vital dan Menarik, 21. Jan Hendriks, Jemaat Vital dan Menarik, 22. 14 Bdk., Heitink, Teologi Praktis, 37. 13 3 1977, 1979, 1983, 1994, 1996, 1997, 1999.15 Pengalaman yang sama juga terjadi di Kalteng, lebih dari 18 kali konflik; tahun 1972, 1982, 1983, 1996: 2 kali, 1997:2 kali, 1998, 1999: 4 kali, 2000: 3 kali, 2001 terbesar dan meluas di seluruh Kalteng.16 Telah banyak pendapat yang membicarakan tentang sebab-musabab fenomena konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura. Syarif Alqadrie,17 menyimpulkan telah terjadi marjinalisasi dalam konteks peranan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam konteks ini, orang Dayak diasumsikan tidak mendapatkan keadilan dari sistem yang ada, sehingga melampiaskan kejengkelan terhadap orang Madura. Namun persoalannya adalah, sulit memahami hubungan langsung perlawanan etnis Dayak akibat marjinalisasi dan hubungannya terhadap etnis Madura. Dengan kata lain, mengapa etnis Madura yang menjadi kambing-hitam sebagai sasaran pelampiasan kemarahan etnis Dayak? Pendapat lain, seperti diungkapkan Djuweng dan Soelaiman,18 lebih menekankan adanya perbedaan latar belakang budaya antara etnis Dayak dan etnis Madura. Baik Dayak maupun Madura, sama-sama memelihara dan mempertahankan identitas kultural etnis mereka. Artinya, baik Dayak maupun Madura menempatkan kelompok etnis mereka sebagai “wadah” sosial untuk membentuk identitas kulturalnya yang saling berbeda sehingga muncul pemicu konflik di antaranya. Dalam tulisan ini, penulis akan menelusuri dan memahami akar penyebab konflik antara orang Dayak dan orang Madura dalam perspektif relasi kultural. Ada banyak dimensi dalam sebuah budaya, salah satu dimensi tersebut adalah bagaimana seseorang, kelompok 15 Edi Petebang, Sejarah Perang Suku di Kalimantan Barat; dalam Majalah Kalimantan Review, (Pontianak, IDRD, 1999), Edisi Oktober, No. 50, 10. 16 Usop dan Bahing Jimat, “Kronologis Sejarah Konflik Etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah”, dalam : Tim Investigasi (peny) Konflik Etnis Sampit: Kronologis, Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran (Palangkaraya, LMMDDKT, 2001), 26. 17 Giring, Citra Madura di Mata Dayak, Dari Konflik Ke Rekonsiliasi, ( Yogjakarta, Galang, 2004 ), h, 1 – 3. 18 Situmorang (ed), Sisi Gelap Kalimantan Barat: Perseteruan Etnis Dayak-Madura, (Pontianak, ISAI & IDRD, 1999) 163, 172. 4 tertentu berhubungan (membangun relasi) dengan orang, kelompok lain. Bentuk relasi yang dibangun seseorang dengan orang lain bukanlah tanpa dasar yang sama sekali kosong. Ada dua aspek yang mendasari bagaimana seseorang membangun relasi dengan orang lain. Pertama, aspek eksternal yaitu pengaruh pengetahuan yang diperoleh seseorang, kelompok tertentu sebagai reaksi atas gambaran sikap dan tindakan orang, kelompok lain selama bergaul. Kedua, aspek internal yaitu pengaruh pengetahuan seseorang, kelompok tertentu atas sistem nilai budaya yang bersangkutan. Intinya, relasi sosial antar seseorang, kelompok tertentu dengan orang, kelompok lain akan sangat dipengaruhi oleh; baik, pengetahuan sebagai reaksi atas sikap dan tindakan yang dilakoni oleh pihak lain terhadap dirinya, maupun pengaruh pengetahuan atas nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka hubungan pergaulan antar seseorang, kelompok tertentu dengan orang, kelompok lain dalam masyarakat majemuk, relasi sosial sebagai titik temu dan titik tengkar antar orang, kelompok yang berbeda. Menurut Tridayakisni melalui relasi sosial, bukan hanya terjadinya pertemuan antar orang, kelompok yang berbeda, tetapi juga pertemuan antar nilai, tradisi yang dianut masing-masing pihak tersebut.19 Dalam pertemuan tersebut, terjadinya proses menilai dan dinilai, sehingga kategori baik atau buruk seseorang, kelompok tertentu, serta nilai-nilai yang dianutnya segera diketahui oleh orang, kelompok lainnya. Dalam konteks di atas, maka relasi sosial berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan berkaitan dengan “tahu”, “mengerti” setelah melihat, mengalami, dan menyaksikan.20 Artinya pengetahuan akan segala sesuatu diperoleh melalui apa yang dilihat, dialami dan disaksikan. Melihat menggambarkan adanya perhatian atau memberikan perhatian 19 20 Bdk., Tridayakisni, dkk, Psikologi Lintas Budaya: Realitas Pertemuan Budaya, (Malang, UMM-Press 2002), 2. Peter dan Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta, Modern English Press, 1991), 1507. 5 kepada sesuatu.21 Dengan melihat akan menyadarkan kita tentang sesuatu. Kesadaran kita akan sesuatu akan semakin mendalam ketika kita juga mengalami, atau ketika kita menyaksikan sesuatu tersebut terjadi pada orang lain. Sikap berkaitan dengan “pendapat” atau “pendirian” tertentu22 yang mendahului tindakan. Pendapat adalah buah pikiran, anggapan, atau prakiraan, yang kita simpulkan atas sesuatu. Itu berarti, sikap adalah keyakinan yang diasosiasikan secara afektif (bagaimana perasaan seseorang tentang sikapnya), dan meliputi unsur kognitif, artinya keyakinan-keyakinan apa yang ada pada seseorang tentang sikapnya23. Tindakan, berkaitan dengan perbuatan, aksi, atau sesuatu yang kita kerjakan.24 Dengan demikian, tindakan merupakan tanggapan spontan didasarkan pada pengetahuan dan sikap yang telah terbentuk.25 Dalam konteks di atas, relasi sosial dapat dipahami sebagai, hubungan pergaulan antar individu, kelompok tertentu didasari atas: pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap orang, kelompok lain, yang diperoleh melalui; apa yang mereka lihat, alami, dan saksikan, selama dalam pergaulan yang terjadi di tempat umum. Tempat umum adalah sebuah ruang fisik (pasar, jalan, tempat kerja, tempat hiburan, dan sebagainya) yang dipergunakan bagi kegiatan bersama, baik secara pribadi, kolektif, dan bersama, untuk pemenuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.26 Pengetahuan, sikap dan tindakan tertentu, terhadap orang, kelompok tertentu, oleh orang atau kelompok dari etnis lain, akan mempengaruhi pola-pola sikap dan tindakan tertentu ketika relasi terjadi. Berkaitan dengan fokus perhatian tulisan ini yakni rusaknya relasi antara etnis Dayak dan etnis Madura, maka akan dipahami lebih mendalam tentang, pengetahuan, sikap dan tindakan apa saja yang mewarnai relasi antar keduanya selama ini? 21 Bdk., John Paul Lederach, Transformasi Konflik, Sebagaimana diterjemahkan oleh Daniel K. Listijabudi, (Yogyakarta, PSPP-UKDW, Duta Wacana University Press, 2005), 17. 22 Peter dan Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, 1442. 23 Suwarsih, Stereotipe Etnis Dalam Masyarakat Multietnis, ( Yogyakarta, Mata Bangsa, 2002), 62-63. 24 Peter Salim , Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1617. 25 Bdk., Suwarsih, Stereotipe Etnis Dalam Masyarakat Multietnis, 79. 26 Parsudi Suparlan “Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar Suku Bangsa”, dalam Wibowo (ed), Reintropeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina, ( Jakarta, Gramedia, 1997), 49. 6 Dalam relasi antar orang, kelompok, dan etnis tertentu, juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dianut atas nilai-nilai kulturalnya. Artinya relasi antar etnis yang berbeda, dipengaruhi oleh sistem nilai budaya (sistem suku) masing-masing pihak yang bersangkutan.27 Hal itu disebabkan, setiap orang, kelompok dari masing-masing suku memiliki sistem sebagai acuan dan pedoman baik nilai maupun tradisi yang dianut. Menurut Albert Rufinus, nilai-nilai budaya yang dianut tersebut mencerminkan pada totalitas hidup, misalnya cara berpikir, berperasaan, bertingkah-laku, hubungan sosial, baik dengan sesama, alam maupun ilahi.28 Dalam nilai-nilai tersebut terkandung kaidah sosial yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Kaidah sosial (nilai adat-budaya) dalam masyarakat merupakan ketentuan-ketentuan dan peraturan umum tentang sikap hidup manusia yang menurut penilaian baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam konteks itu, budaya dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial.29 Artinya, nilai budaya yang dianut oleh etnis tertentu, akan mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan etnis tersebut dalam membangun hubungan dengan warga dari etnis lain. Berkaitan dengan relasi kultural antara etnis Dayak dan Madura, kajian ini tidak membahas budaya secara luas, melainkan hanya mencermati sub budaya tertentu yang mewarnai relasi antar keduanya, dan terkait dengan akar konflik. Untuk itu, kultur kekerasan tersebut dan unsur-unsurnya akan dipahami maknanya sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.30 Pertanyaannya adalah tradisi dan nilai apa yang dianut oleh baik etnis 27 Parsudi Suparlan, Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar Suku Bangsa, 50. Albert Rufinus, “Budaya Dayak” dalam Nicoandasputra (ed), Mencermati Dayak Kanyatn, (Pontianak, IDRD, 1997), 55. 29 Bdk., Spradley, “Foundations of Cultural Knowledge”, dalam Culture, and Cognitions Rules, Maps and Plan, (San Fransico, Chandler Publishing Company, 1972), 9. 30 Latif Wiyata, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, (Yogyakarta, LkiS, 2002), 9. 28 7 Dayak maupun etnis Madura dalam relasinya selama ini, sehingga menyebabkan terjadinya konflik berulang kali? Menurut Usop,31 dalam rangka menjalin relasi dengan orang, kelompok lain, warga dari etnis Dayak selain sangat menjunjung tinggi nilai adat-budaya, juga menganut nilai keterbukaan, ramah-tamah, cinta damai, dan suka mengalah. Artinya, etnis Dayak dalam relasinya sangat terbuka kepada siapapun. Keterbukaan dalam bergaul, juga diiringi sifat polos, ramah, dan suka memendam perasaan terhadap orang lain. Keterbukaan dalam relasi bisa terjadi dengan siapapun, termasuk dengan etnis Madura. Bahkan menurut Simal Penyang, nilai keterbukaan, keramah-tamahan, cinta damai dan suka mengalah dalam berelasi dengan siapapun sudah berlaku sejak tradisi rumah panjang.32 Nilai-nilai tersebut bukan hanya dianut, melainkan juga membentuk pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya membangun relasi dengan pihak lain. Namun, walaupun orang Dayak bersikap terbuka, ramah-tamah, cinta damai dan suka mengalah kepada siapapun, jika nilai-nilai kultural yang dijunjung tingginya itu kemudian dilanggar oleh pihak lain (salah satu warganya dilukai sampai mengeluarkan darah, tewas, dan pelakunya tidak taat terhadap adat yang berlaku) maka semua komponen suku Dayak akan melawan siapapun yang melecehkan. Catatan sejarah peradaban masyarakat Dayak telah menujukkan, dalam rangka membela dan melawan pihak-pihak yang melecehkan nilai-nilai dan harga diri dalam relasi, masyarakat Dayak pernah menganut tradisi kekerasan kayau-mengayau.33 Mengayau adalah tindakan kekerasan dengan membunuh orang yang dianggap sebagai musuh yaitu memenggal kepala dan mengambil tengkoraknya. Tindakan pengayauan akan dilakukan dalam masyarakat 31 Amu Linu (ed), Majelis Adat Dayak Kalteng Menjawab Tantangan Terjadinya Kerusuhan di Kalimantan Tengah, Edisi kedua, (Palangka Raya, PPKD-LP Unpar, 2002), 55 – 69. 32 Amu Linu, (ed), Majelis Adat Dayak, 41. 33 Edi Petebang, Dayak Sakti: Mengayau, Tariu, dan Mangkok Merah, ( Pontianak, IDRD, 1998), 1-2. 8 Dayak, apabila ada warga suku Dayak yang luka, terbunuh (tewas) secara sia-sia oleh pihak luar. Dalam konteks itu, pelaku bukan hanya melukai atau membunuh, melainkan juga dianggap telah melanggar nilai-nilai luhur yang berlaku. Dengan demikian, pelaku pembunuhan bukan hanya dianggap sebagai ancaman atau musuh, tetapi juga diyakini telah melecehkan dan melanggar nilai adat suku Dayak yang terbuka, ramah-tamah, cinta damai dan suka mengalah. Untuk menegakkan kembali nilai-nilai luhur yang dianut dan kehormatan suku yang telah dilecehkan oleh pihak luar, maka tindakan mengayau dapat dilakukan. Artinya, salah satu motif dari tradisi kayau erat kaitannya dengan balas dendam, terutama apabila ada warganya yang terluka atau tewas secara sia-sia oleh pihak luar.34 Namun, tindakan mengayau bukan semata-mata untuk membalas dendam tetapi juga sebagai bentuk penegakkan kembali nilainilai luhur yang telah dijadikan standar ukuran dalam relasi sosial. Intinya anggapan telah terjadinya pelecehan terhadap nilai yang dianut bisa menjadi alat pembenar untuk melakukan tindakan pengayauan. Sasaran pengayauan biasanya adalah orang, kelompok, suku tertentu yang dianggap sebagai musuh. Kata musuh menunjukkan pada orang, kelompok, yang telah menodai dan melecehkan nilai-nilai hidup bersama yang dianut oleh orang Dayak, misalnya melakukan pembunuhan terhadap salah satu warga Dayak, kemudian tidak patuh terhadap hukum adat yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah etnis Dayak menilai bahwa etnis Madura dalam relasinya selama ini dominan nyata telah melecehkan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga memaksa orang Dayak yang sebelumnya bersikap terbuka dan ramah-tamah tiba-tiba berubah menjadi ganas dan beringas yang disertai aksi-aksi kekerasan seperti dalam relasi sosial selama ini? 34 Edi Petebang, Dayak Sakti, 16 9 Menurut Edi Petebang, tradisi kekerasan kayau-mengayau dalam masyarakat Dayak sebenarnya sudah secara resmi dihentikan melalui “Perjanjian Tumbang Anoi” di Kalimantan Tengah pada tahun 1894.35 Sejak perjanjian tersebut, tidak dibenarkan lagi adanya tradisi memburu kepala, perbudakan (kayau) dalam masyarakat Dayak. Unsur-unsur yang mendorong terjadinya pengayauan, misalnya balas dendam, tidak seharus dibayar dengan nyawa atau darah, cukup dengan mematuhi penegakan adat yang berlaku. Namun Usop juga mengakui, jika kelangsungan hidup suku Dayak terancam oleh kekuatan luar karena nilai-nilai yang dijunjung tinggi dilecehkan, dan penegakan adat tidak dipatuhi, maka semangat mengayau akan muncul.36 Sejak masuknya agama resmi, misalnya Kristen, Islam dan faktor pendidikan terhadap orang Dayak, budaya kayau sudah ditinggalkan. Bahkan Ukur mengatakan, masuknya agama Kristen sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi suku Dayak untuk tidak lagi meneruskan tradisi kayau, dan perbudakan.37 Itu berarti pada saat ini, masyarakat Dayak yang berpendidikan dan menganut agama resmi tidak menganut budaya kayau. Pertanyaannya, mengapa semangat kekerasan kayau muncul kembali dalam konteks relasi antara etnis Dayak dan etnis Madura? Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelusuri pula perspektif orang Madura dalam membangun relasi sosialnya dengan pihak lain. Latief Wiyata38 menegaskan, dalam tradisi masyarakat Madura, relasi sosial antar sesama dikenal dalam dua istilah penting, yaitu “bala” atau pertemanan dan “moso” atau musuh. Moso adalah seseorang, atau kelompok yang 35 Amu Linu (ed), Majelis Adat Dayak, 3. Amu Linu (ed), Majelis Adat Dayak, 25 – 27. 37 Lihat F, Ukur, Tantang Djawab Suku Dajak, ( Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1971), 81; bdk., Ukur, Tuaiannya Sungguh Banyak: Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835, ( Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2000), 145. 38 Latief Wiyata, Carok, 61- 62. 36 10 dianggap musuh dan harus dibunuh. Kalimat harus menunjukkan kepastian, kapanpun (cepat atau lambat) pembunuhan terhadap orang yang dianggap musuh pasti dilakukan. Menurut Latief, moso terbagi dua: moso dalem yaitu musuh dari lingkungan keluarga sendiri dan moso lowar adalah musuh yang tidak mempunyai ikatan apapun. Baik moso dalem ataupun moso lowar, masih dibedakan lagi menjadi moso mata dan moso ate. Moso mata adalah seseorang atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai musuh diakui secara terang-terangan sehingga pembunuhan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Moso ate adalah seseorang, kelompok yang dalam pergaulan sehari-hari tidak secara terang-terangan dianggap musuh, bahkan sebaliknya diperlakukan seolah-olah sebagai teman (kanca rapet). Dalam suasana ini, orang yang dianggap sebagai musuh dibuat agar tidak menyadari, bahwa jiwanya terancam. Dalam situasi lengah (korban tidak siap senjata, tanpa menyadari), maka pembunuhan dapat dilakukan.39 Pembunuhan terhadap seseorang yang dianggap sebagai musuh dalam masyarakat Madura dikenal dengan istilah carok. Carok dimulai dengan cara “nyekep” yaitu kemana saja selalu membawa senjata tajam.40 Pelaksanaan carok bisa dengan “nyelep” yaitu dengan cara sembunyi, main belakangan, atau cara curang; calon korban tidak menyadari bahwa, yang bersangkutan akan diserang atau dibunuh.41 Carok juga bisa dengan cara “ngonggai” yaitu terbuka atau sportif; artinya kedua belah pihak yang akan terlibat carok, sama-sama mempersiapkan diri, baik dalam hal senjata, maupun bantuan teman atau apagar.42 Pertanyaannya, apakah etnis Madura yang ada di Kalimantan, khususnya di Sampit, menganggap etnis Dayak sebagai moso mata 39 Latief Wiyata, Carok, 61. Latief Wiyata, Carok, 169. 41 Latief Wiyata, Carok, 170. 42 Latief Wiyata, Carok, 169-175. 40 11 atau moso ate, sehingga tradisi carok cenderung dikedepankan ketika terjadi persoalan dalam berelasi? Menurut Nagian Himawan,43 tidak semua warga Madura menerima budaya carok, terutama golongan terdidik dan agamawan. Ada tiga golongan dalam masyarakat Madura. Pertama, santri adalah golongan terdidik, dan agamawan. Golongan ini menentang adanya budaya kekerasan carok. Kedua, golongan bleter, adalah kelas menengah (pendidikan: SMP / SMA) golongan ini masih mudah diatur dan masih bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Ketiga, adalah beijing / bajingan, adalah golongan kebanyakan dalam masyarakat Madura. Golongan beijing rata-rata tidak terdidik (buta huruf, tidak tamat SD) dan tidak taat dengan ajaran agama. Kecenderungan sebagian dari golongan beijing suka ulah kriminal seperti judi, mabuk, mencuri, temperamental, dan mudah naik pitam. Perilaku yang keras, kasar, temperamental itulah yang mengakibatkan kerusakan relasi dengan orang lain. Persoalannya adalah, ketika terjadinya gesekan sosial (perkelahian, rebutan bisnis, perempuan) dalam relasi sosial dengan warga dari etnis lain (Dayak) penyelesaiannya selalu mengedepankan cara-cara kekerasan seperti tradisi carok. Tradisi carok digunakan dalam rangka mempertahankan harga dan kehormatan diri, karena mungkin saja pada saat terjadinya gesekan sosial itu, oknum (Madura) yang bersangkutan merasa dipermalukan, dilukai hatinya misalnya ditegur di depan umum.44 Menurut Nagian, kebanyakan warga Madura yang berada di Kalimantan adalah dari golongan beijing.45 Dalam bekerja golongan ini tidak mengutamakan pekerjaan yang bersyarat 43 Hasil wawancara penulis dengan Nagian Himawan (Tokoh Mahasiswa Madura) di Pontianak, tanggal, 6 April 1999, dapat dilihat dalam: Paulus Ajong, “Konflik Dayak – Madura di Kalimantan Barat: Suatu Kenyataan dan Tantangan bagi Rekonsiliasi”: dalam Nancy Souisa (ed) Geliat berpikir Mahasiswa Teologi dari Barat hingga Timur, (Jakarta, PERSETIA, 2002), 34; bdk., Nagian Himawan, “Orang Madura di Mata Madura”: dalam, Edi Petebang, Sutrisno, Konflik Etnik di Sambas, ( Jakarta, ISAI, 2000), 33 – 35. 44 Latif Wiyata, Carok, 232. 45 Nagian Himawan, Kalimantan Review, (Pontianak, Edisi, April 1999), 34. 12 akademis tertentu, melainkan pekerjaan yang mengandalkan otot atau tenaga. Hasilnya adalah kebanyakan para perantau Madura di Kalimantan terutama dari golongan beijing ini menguasai pekerjaan menengah ke bawah. Pada saat bersamaan, warga Madura tersebut akan bersentuhan langsung dengan penduduk setempat yang juga menekuni tingkatan pekerjaan yang sejajar. Persoalannya akan muncul ketika warga Madura yang bersentuhan langsung dengan penduduk lokal adalah kebanyakan golongan beijing yang masih kental tradisi carok. Kebiasaan budaya carok inilah yang diyakini salah satu penyebab utama konflik antar kedua belah pihak terjadi terus-menerus, termasuk konflik dasyat antara etnis Dayak dan etnis Madura pada tahun 2001 di Sampit. Konflik Sampit tahun 2001 tetap meninggalkan dampak. Dampak konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura selain jatuhnya korban jiwa-raga, musnahnya harta benda di kedua belah pihak yang jumlah korban sulit dipastikan, pengungsi besar-besaran, juga berdampak pada relasi sosial antar kedua etnis di masa mendatang.46 Dalam tulisan ini hanya memfokuskan pada dampak konflik bagi relasi sosial antar kedua etnis tersebut di masa depan, secara khusus pasca pengembalian pengungsi Madura ke tempat semula yaitu di Kalimantan. Ada beberapa dampak negatif bagi relasi sosial antar kedua belah pihak di masa mendatang. Pertama, adanya perasaan kebencian yang mendalam antara Dayak dan Madura pada tingkat arus bawah. Kedua, adanya perasaan saling ketidakpercayaan baik pihak Dayak terhadap pihak Madura, maupun ketidakpercayaan pihak Madura terhadap pihak Dayak. Ketiga, munculnya rasa kesukuan yang tinggi baik di pihak Madura maupun di pihak Dayak.47 46 Jumlah Madura di Kalteng sebelum konflik hingga th 1999: 117.000 orang dari total 1. 7 juta populasi keseluruhan di Kalteng hingga th 2000. Pengungsi Madura akibat konflik Sampit mencapai 56.000, sebagian besar sudah dikembalikan ke Sampit bulan September 2004. Sisa yang masih berada di Madura hanya 13.000 pengungsi, dalam, Koran Tempo “Menyunat Dompet Pengungsi Sambas”, 2 Februari 2005, 16. 47 Human Rights Watch Asia, Konflik Etnis Di Kalimantan Barat, (Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 1998), 4. 13 Dampak tersebut semakin mewarnai rusaknya relasi sosial antara warga Dayak dengan warga Madura selanjutnya. Sejalan dengan rusaknya relasi, maka semakin menimbulkan kebencian dan dendam antar keduanya, yang turut mengentalkan sentimen dan solidaritas atas nama suku. Mengentalnya segregasi (pemisahan) atas dasar suku, akan merenggangkan ikatan-ikatan persaudaraan sebagai sesama manusia. Kondisi demikian menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun, apabila dalam relasi kembali antar kedua belah pihak terjadinya gesekan sosial atau pemicu misalnya terjadinya perkelahian, perebutan lahan usaha, masalah perempuan, pencurian, dan sebagainya yang melibatkan warga dari kedua belah pihak. Selain adanya fakta-fakta konflik dan dampak negatifnya bagi hubungan kedua etnis di atas, saat ini juga ada fakta bahwa, baik pemerintah pusat maupun daerah (Pemda Sampit) menginginkan agar para pengungsi segera dikembalikan ke tempat semula yakni daerah tempat terjadinya konflik. Begitu juga para pengungsi etnis Madura yang berada di pengungsian, berkeinginan keras untuk segera kembali ke tempat asalnya yakni di Kalimantan Tengah, khususnya Sampit. Pada saat ini, keinginan tersebut sudah dilaksanakan, dengan pengembalian pengungsi etnis Madura yang ada di pengungsian (Jawa Timur) ke Kalimantan Tengah. Bahkan sejak September 2004 sebagian besar pengungsi Madura sudah kembali ke daerah asal seperti di Sampit (pengungsi yang belum kembali tersisa 13.000 dari 56.000 jiwa).48 Dengan kembalinya para pengungsi Madura ke Sampit berarti relasi sosial antara warga Dayak dan warga Madura selanjutnya pun akan terjadi. Pertanyaannya adalah, akankah konflik yang ditandai aksi-aksi kekerasan kembali terjadi di masa depan? Dalam konteks persentuhan kembali, tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak, baik Dayak maupun para pengungsi Madura dalam membangun relasi sosial selanjutnya masih dipengaruhi pengetahuan, sikap dan tindakan seperti pada saat pra konflik. Kondisi 48 Koran Tempo, Menyunat Dompet Pengungsi Sambas, 2 Februari 2005, 16. 14 relasi sosial selanjutnya masih ibarat bara dalam sekam. Artinya relasi sosial selanjutnya masih mengandung kerawanan terjadinya pengulangan konflik dan aksi kekerasan, terutama apabila adanya pemicu atau gesekan sosial dalam masyarakat. Padahal sulit dijamin apabila gesekan sosial dalam relasi selanjutnya tidak akan terjadi. Gambaran tersebut, menunjukkan adanya massa mengambang akan kepastian masa depan yang rawan provokasi dan isu, sehingga memungkinkan aksi-aksi kekerasan tetap terjadi.49 Berdasarkan gambaran di atas, pertanyaannya adalah, darimana dan bagaimana seharusnya memulai relasi sosial antar kedua etnis tersebut di masa mendatang agar lebih positif? Dalam konteks itu, relasi sosial antar keduanya pasca konflik tetap menjadi tantangan yang masih berpotensi terjadinya pengulangan konflik apabila ada pemicu. Namun pada saat yang bersamaan, terjadinya relasi kembali antar kedua etnis tersebut juga sebuah kesempatan besar.50 Kesempatan dimaksud karena terbukanya kemungkinan untuk membangun relasi baru yang lebih positif di masa depan. Relasi baru yang positif itu sangat tergantung pada masingmasing pihak; apakah mau belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian terbuka mengoreksi dan membaharui kesalahan tersebut dalam relasi sosial selanjutnya? Berdasarkan harapan di atas, membangun relasi sosial yang lebih positif antar kedua belah pihak pasca konflik merupakan tantangan bagi semua pihak, termasuk Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). Hal itu mengingat, GKE ditempatkan dan menempatkan diri di tengah-tengah fakta adanya kecenderungan aksi-aksi kekerasan yang mewarnai persentuhan antara warga Madura dengan warga Dayak, termasuk di antaranya adalah anggota jemaat 49 Menurut pengalaman konflik etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat, pernah diadakan perdamaian bahkan ada tugu perdamaian di Samalantan, sebagai simbol tidak ada lagi permusuhan antar ke dua suku tersebut, namun simbol perdamaian tersebut juga menjadi saksi kehancuran hubungan kedua suku, dengan pecahnya konflik dasyat tahun 1996-1997. Hal tersebut, akibat kurangnya persiapan, pemulihan dampak psikologis: dendam, emosi, benci, tidak percaya di antara kedua suku terkait. Bdk., Edi Petebang, Konflik Etnik, (Pontianak, ISAI, 2000), 94. 50 Bdk., Psykologi Sosial Lintas Budaya Tri Dayakisni, 2. 15 GKE.51 Pertanyaan adalah, apa yang harus GKE lakukan dalam rangka memberi sumbangan untuk membangun relasi sosial yang lebih positif di masa depan? Dalam konteks itu, GKE sebagai gereja yang mengemban misi Allah dalam Yesus Kristus dan berhadapan langsung dengan kenyataan kerusakan relasi sosial antar sesama, diharapkan turut memberikan sumbangan pemikiran atau wacana teologis berdasarkan kehendak Allah. Pemikiran teologis yang diharapkan dalam konteks kerusakan relasi sosial antar sesama di atas, berkaitan dengan wacana tentang bagaimana “seharusnya membangun relasional etis dengan orang lain” berdasarkan intisari pengajaran Yesus. Menemukan dan menawarkan pemikiran teologis di atas adalah tantangan bagi semua warga GKE, termasuk para pendetanya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis bukan hanya berusaha menelusuri akar penyebab kekerusakan relasi sosial antar warga Dayak dan warga Madura, melainkan juga hendak menawarkan pemikiran teologis, sebagai masukan atau landasan orientasi relasional etis warga GKE dengan orang lain selanjutnya. Berdasarkan kepentingan itu, penulis tidak membiarkan wacana teologis tersebut terlepas dari teks-teks Alkitab. Adapun teks-teks Alkitab yang dijadikan dasar wacana tersebut adalah teks Lukas 10:25-37 sebagai titik konsentrasi dan teks Lukas 6:12-42 sebagai bahan penunjang. Pertanyaannya adalah, sumbangan makna apa dari intisari pengajaran Yesus tersebut yang bisa dijadikan masukan bagi warga Dayak GKE dalam membangun relasi sosial selanjutnya? 51 Gerrit Singgih pernah memberikan kritik, terhadap agama Kristen, termasuk GKE karena, di tengah-tengah konflik etnis yang terjadi, gereja (GKE) tidak memberikan reaksi terhadap konflik, malah ada kesan merujuk pada tradisi nenek moyang yang diwarisi. Dalam, Gerit Singgih, Mengantisipasi Masa Depan, Berteologi Dalam Konteks di Awal Milinium, ( Jakarta, BPK, Gunung Mulia, 2004), 140. 16 C. Batasan Masalah Dalam perumusan permasalahan tesis ini, penulis akan membatasi kajian terhadap etnis Dayak. Pembatasan ini perlu, mengingat etnis Dayak beraneka-ragam sub-sub suku Dayak misalnya Dayak Ngaju, Maanyan, Ot Danum, dan sebagainya. Batasan masalah dalam tesis ini tidak didasari atas nama sub-sub suku tersebut, melainkan dalam hal keyakinan masyarakat Dayak seperti, Kristen, Katolik, Hindu Kaharingan, Islam. Sasaran kajian sebagai lingkup studi ini adalah pihak Dayak yang beragama Kristen dan menjadi warga jemaat GKE (Dayak GKE). Jemaat GKE yang menjadi sampel penelitian juga dibatasi lagi, yakni jemaat GKE Sampit.52 Pengalaman tersebut juga dihubungkan dengan pengalaman kekerasan antara Dayak dengan etnis Madura tahun 2001 yang terjadi di kota Sampit. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dan harus diteliti berkaitan “relasi” warga Dayak GKE dengan Madura selama ini. Pengetahuan, sikap dan tindakan apa saja yang dianut warga jemaat Dayak GKE dalam relasi dengan etnis Madura setelah melihat, mengalami, dan menyaksikan selama bergaul dengan warga Madura di Sampit?. Saat ini, pengungsi Madura sudah kembali lagi ke Sampit. Itu berarti terbuka kembali hubungan pergaulan antara jemaat Dayak GKE dengan etnis Madura. Dalam konteks itu, GKE Sampit sangat penting dalam memberikan masukan-masukan pengetahuan, sikap, dan tindakan warga jemaat dalam berelasi. Artinya relasi yang diwujudkan oleh anggota jemaat, bukan hanya atas dasar nilai dan tradisi masyarakat Dayak yang dianut selama ini, tetapi juga nilainilai keyakinan yang ditanamkan GKE melalui pembangunan jemaatnya. 52 Mengingat luasnya sub-sub suku Dayak, maka tulisan ini hanya mempokuskan pada etnis Dayak yang telah menjadi warga jemaat GKE. Suku Dayak adalah sebutan umum untuk suku-suku asli yang mendiami pulau Kalimantan, yang terdiri dari sub-sub suku Dayak, misalnya saja di Kalimantan Barat ada 450 sub-sub suku, belum lagi sub-suku di Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur. Walaupun adanya perbedaan bahasa, namun kebudayaan secara umum adanya kesamaan: mandau, sumpit, tembikar, dan kedudukan wanita. Dapat dilihat: F. Ukur, Kebudayaan Dayak: Paulus florus (ed), Budaya Dayak, Pontianak, IDRD, 1992, 126. 17 Sebagai tesis di bidang teologi praktika, penulis akan memusatkan perhatian pada teologi yang berorientasi pada relasi positif antar sesama sebagai dasar acuan bagi pembangunan jemaat. Terutama dalam konteks terjadinya relasi kembali warga jemaat Dayak GKE dengan pengungsi warga Madura yang ada di Sampit. Latar belakang budaya etnis Dayak, sekaligus pendeta GKE yang dimiliki penulis akan sangat mewarnai cara berpikir penulis dalam mengangkat permasalahan tesis ini. Masalah akan dibatasi sebagai berikut: 5. Unsur-unsur apa saja yang dapat dipahami melalui relasi kultural warga Dayak yang menjadi anggota jemaat GKE Sampit dengan warga Madura, yang mendorong terjadinya konflik ? 6. Bagaimana hubungan pengetahuan yang dimiliki oleh warga Dayak baik atas nilai-nilai yang dianutnya, maupun reaksi terhadap sikap dan tindakan warga Madura bisa dipahami mempengaruhi aksi-aksi kekerasan? 7. Teologi relasi yang bagaimana perlu ditanamkan dalam pembangunan jemaat sebagai dasar pengetahuan, sikap dan tindakan warga Dayak GKE dalam relasinya dengan masyarakat sekitarnya termasuk dengan warga Madura selanjutnya? D. Judul Tesis: Menguak Bara dalam Sekam: Suatu Tantangan bagi Pembangunan Jemaat GKE dalam Membangun Relasi Positif Pasca Konflik Etnis Dayak-Madura di Sampit 18 E. Hipotesis 5.1.Adanya kesamaan kultur kekerasan antara kedua etnis dalam relasinya selama ini, seperti: tradisi carok dalam masyarakat Madura, dan semangat mengayau dalam masyarakat Dayak. Konflik destruktif akan terjadi, ketika dalam pemenuhan ekonomi, sosial, budaya, yang terjadi di tempat umum, masing-masing pihak dalam tawarmenawarnya, menonjolkan simbol-simbol, atribut budayanya untuk menilai dan dinilai. Mengangkat atribut, simbol khas masing-masing suku akan meraih sentimen kesukuan, apalagi dikaitkan dengan harga dan kehormatan diri yang seolah-olah telah dinodai dan dirusak oleh pihak lawan. 7.0. Adanya kecenderungan warga Dayak menjadikan pengetahuannya atas nilai-nilai yang dianut sebagai tolok ukur dalam menilai sikap dan tindakan warga Madura yang berdampak pada pembenaran diri. 7.0. Pemahaman subjektif dan saling curiga akibat buruknya komunikasi antar kelompok Dayak dan kelompok Madura mempengaruhi buruknya relasi sosial antar kedua kelompok. F. Tujuan Penulisan Tesis ini ditulis dengan tujuan agar GKE secara umum, dan GKE Sampit secara khusus menjadi lebih sadar dan peka terhadap konteks kegelisahan atas rusaknya relasi sosial antar etnis akibat konflik yang kerapkali terjadi di Kalimantan. Kesadaran GKE selama ini untuk menciptakan suasana dan relasi damai, dengan dilaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang perdamaian merupakan langkah positif. Namun kesadaran tersebut jangan hanya berhenti dalam taraf kegiatan formal (seminar, lokakarya) saja, 19 melainkan harus diwujudnyatakan dalam bentuk pemberdayaan ke dalam pula yang diarahkan kepada anggota jemaatnya secara konkret. Pemberdayaan dimaksud seperti mencari, menemukan dan menjemaatkan pemikiran atau wacana teologis yang bisa menguatkan iman umat pasca konflik, sekaligus bisa dijadikan pegangan mantap dan masukan bagi pengetahuan, sikap dan tindakannya dalam membangun relasi sosial yang positif selanjutnya. Wacana teologis tentang relasi positif tersebut diharapkan bisa menjadi “roh” gereja dalam membangun jemaatnya. Hasil yang diharapkan adalah anggota jemaat GKE menemukan dan terhisap dalam ruang kesadaran tentang pentingnya menjalin relasi dengan semua orang, tanpa pandang bulu secara positif berdasarkan kesadaran imannya. Untuk itu kesadaran pembangunan jemaat yang menekankan relasi positif dan berlaku bagi semua manusia menjadi penting. Kesadaran tersebut atas dasar bahwa setiap persoalan yang terkait pada anggota jemaat dan masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari pembangunan jemaat sekaligus merupakan tanggung-jawab gereja untuk memberikan masukan pelayanan secara benar. Dalam konteks itu, barulah peran gereja bukan hanya menjadi fasilitator atau subyek perdamaian, melainkan telah memberdayakan warganya, sehingga umat atas kesadarannya kemudian menjadi pelaku yang menghadirkan nilai perdamaian pula di tengah-tengah kerusakan relasi sosial antar sesama.53 Harapan penulis melalui tesis ini adalah, pikiran dan wacana yang belum muncul di kalangan anggota jemaat GKE dari etnis Dayak mengenai konsep relasi positif menjadi lebih terbuka. Jika hal ini dibangun, maka GKE dapat memberikan masukan; kritik dan perbaikan yang sangat berharga terhadap semua komponen terkait seperti; warga Dayak, warga Madura, lembaga adat, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintah. 53 Rob van Kessel, 6 Tempayan Air, 7. 20 G. Kerangka Teoritis Setiap orang, kelompok, memiliki kompleksitas motivasi.54 Motivasi tersebut distimuli oleh dua sistem hasrat (appetitive system) mendasar yang ada dalam setiap manusia.55 Stimuli dari salah satu hasrat ini menghasilkan perasaan gembira, kepuasan, dan cinta. Stimuli hasrat lainnya menghasilkan sensasi kecemasan, teror dan kemarahan. Dengan demikian, motivasi setiap orang, kelompok mengarah pada bagaimana mencapai kegembiraan, kesenangan, dan kepuasan, dan di sisi lain, bagaimana menghindari diri dari perasaan sebaliknya.56 Dua kehendak mendasar di atas, akan selalu mempengaruhi seseorang, kelompok, untuk mengetahui, bersikap dan bertindak terhadap dunia: baik dalam konteks hubungannya dengan alam, maupun hubungannya dengan sesama. Artinya, seseorang, kelompok, selalu didorong untuk mengetahui segala sesuatu, bersikap dan melakukan (bertindak) sesuatu; baik untuk mencapai sesuatu yang membawa kegembiraan, kepuasan maupun didorong untuk menghindari sesuatu yang bisa membawa pengaruh buruk bagi dirinya. Dengan demikian mengetahui, bersikap dan bertindak merupakan suatu proses yang berada pada tataran kognisi. Pengetahuan disimpan dan diproses dalam pikiran.57 Proses-proses kognisi (pengetahuan, persepsi, dan bentukan konsep) seseorang mempengaruhinya beradaptasi dengan lingkungan.58 Sama halnya pengetahuan, bersikap juga berada dalam tataran kognisi. Sikap-sikap seseorang, sekelompok orang, dikonstruksikan oleh berbagai 54 Ted Robert Gurr, “Deprivasi Relatif dan Kekerasan” dalam Thomas Santoso (ed), Teori-teori Kekerasan, (Surabaya, Gahlia Indonesia & Universitas Kristen Petra, 2002), 64. 55 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 64. 56 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 64. 57 Spradley, “Foundations of Cultural Knowledge”, dalam Culture, and Cognitions Rules, Maps and Plan, (San Fransico, Chandler Publishing Company, 1972), 9. 58 Spradley, Foundations of Cultural Knowledge, 10. 21 pengetahuan kultural yang dimilikinya,59 baik untuk pencapaian segala sesuatu yang bisa membawa kegembiraan dan kepuasan maupun untuk menghindari diri dari pengaruh buruk. Pengalaman dari proses mengetahui, bersikap dan bertindak, baik; siginifikasinya untuk mencapai apa yang diharapkan, maupun signifikasinya menghindari apa yang tidak diharapkan, biasanya dijadikan nilai-nilai standar bagi seseorang, kelompok selanjutnya. Menurut Gurr, nilai adalah acuan, obyek, kondisi yang diinginkan serta dipertahankan sebagai penuntun normatif bagi seseorang, kelompok tertentu, baik untuk mencapai apa yang diharapkan maupun untuk menghindari apa yang tidak diinginkan selanjutnya.60 Namun persoalannya adalah, lingkungan tempat seseorang, kelompok berada selalu berubah-ubah, misalnya dalam hubungan dengan alam: semula alam luas dan berlimpah berubah menipis dan musnah; dalam hubungan dengan sesama: semula populasinya masih jarang berubah menjadi padat dan majemuk.61 Dalam konteks perubahan tersebut, apa yang seseorang, kelompok tertentu pelajari dan cocok untuk situasi dan konteks tertentu, belum tentu selalu cocok untuk situasi dan konteks yang selalu berubah. Dalam konteks perubahan pada masyarakat majemuk (suku, budaya); relasi tersebut bukan hanya pertemuan antar orang, kelompok, tetapi juga pertemuan antar sistem nilai-nilai yang dianut masing-masing suku.62 Artinya, masing-masing etnis akan mengacu pada sistem nilai suku yang bersangkutan, baik; untuk mencapai apa yang diharapkan (kegembiraan, kepuasan) maupun untuk menghindari kondisi yang sebaliknya bagi suku yang bersangkutan. 59 Bdk., Warnen, Stereotipe Dalam Masyarakat Multietnik, 79. Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 66. 61 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 64. 62 Sistem nilai suku adalah tatanan nilai, norma kehidupan yang digunakan oleh warga suku tersebut baik sebagai pribadi maupun kolektif yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai apa yang diharapkan (kegembiraan, kepuasan) maupun untuk menghindari, melindungi diri dari kondisi sebaliknya (kecemasa, teror dan kemarahan). Nilai tersebut berisikan patokan-patokan etika dan moral yang ideal, aktual dan dioperasikan melalui pribadi, keluarga, wilayah suku, pemangku adat, oleh warga suku yang bersangkutan. 60 22 Menurut Gurr,63 seseorang, kelompok bisa mengalami kekecewaan atau ketegangan (frustrasi), apabila pengetahuan, sikap dan tindakan tertentu yang signifikan membawa seseorang, kelompok tertentu mencapai apa yang diharapkan; dan signifikan membawa mereka menghindari pengaruh buruk dalam situasi dan konteks tertentu, namun tiba-tiba dengan pengetahuan, sikap dan tindakan yang sama, ternyata tidak cocok untuk konteks dan situasi yang berubah. Kekecewaan atau ketegangan akan muncul, apabila apa yang hendak diharapkan dapat dicapai, misalnya kegembiraan, kepuasan ternyata tidak terwujud; namun sebaliknya hal-hal yang tidak diharapkan seperti teror, kecemasan dan ketidakpuasan justru itu yang terjadi. Intinya, perasaan kecewa dan ketegangan (frustrasi) muncul disebabkan oleh apa yang diharapkan terjadi (das Solen) tidak terwujud, namun yang terjadi (das Sein) justru yang tidak diharapkan. Menurut Gurr, seseorang, kelompok tertentu yang berada dalam ketegangan, biasanya merasakan dirinya berada dalam kondisi sangat tidak menyenangkan. Kondisi tersebut merupakan sumber fundamental yang memaksa seseorang untuk mengatasi atau menghindarinya.64 Oleh karena itu, seseorang, kelompok tertentu tersebut, sebisa mungkin akan menghindari atau mengatasi; bahkan bila perlu dengan cara-cara yang tidak realitas yaitu agresi-destruktif (penyerangan dengan kekerasan).65 Mengapa demikian? Alasan cukup jelas, karena proses sosialisasi mengajarkan bahwa, manusia didorong untuk mencapai stimuli yang membawa kesenangan, kegembiraan dan berusaha menghindari stimuli yang membawa pengaruh buruk bagi dirinya.66 Tindakan agresi-destruktif merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari atau melepaskan ketegangan yang dialaminya; 63 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 66. Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 71. 65 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 70. 66 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 65. 64 23 terutama ketika ia dipengaruhi oleh stimuli berbahaya secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan tidak dapat dihindarinya dengan cara lain.67 Menurut Gurr dalam konteks relasi antar orang, kelompok tertentu dan orang, kelompok lain, kondisi ketegangan di atas, bisa dialami oleh salah satu pihak atau semua pihak di berbagai arena sosial, termasuk di tempat umum. Tempat umum yaitu ruang fisik seperti pasar, jalan raya, tempat kerja, tempat hiburan dan sebagainya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan secara bersama dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.68 Sistem di tempat umum terbuka bagi para pelaku untuk bertindak dan menempati posisi-posisi sosial sesuai dengan peranan dan fungsinya. Ciri sistem di tempat umum yang diutamakan adalah egaliter, kesetaraan-sederajat, dan kemampuan tawar menawar. Dalam tawar-menawar para pelaku bebas menggunakan kekuatan seperti uang, jasa, fisik, dan sosial. Pada saat tersebut masing-masing pelaku bebas bersikap dan bertindak berdasarkan sistem nilai kesukuan masing-masing.69 Dalam konteks di atas, masing-masing pihak yang berbeda, akan bersikap dan bertindak berdasarkan pengetahuan masing-masing. Pengetahuan tersebut selain bersumber dari sistem nilai-nilai ideal yang telah dianut oleh masing-masing suku, juga dipengaruhi rangsangan eksternal yaitu reaksi atas sikap dan tindakan yang diperankan oleh pihak lain. Bentukan pengetahuan sebagai reaksi dari eksternal tersebut diperoleh melalui apa saja yang dilihat, dialami, dan disaksi melalui alat indera terhadap pola sikap dan tindakan yang ditampilkan pihak lain. 67 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 70. Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 71. 69 Parsudi Suparlan, Reintrospeksi, 53. 68 24 Namun, apa yang dilihat, dialami, dan disaksikan mengalami proses seleksi dan reduksi.70 Artinya hanya perilaku-perilaku yang sensasional atau mencolok saja yang disimpan dalam otak atau pikiran. Ketika dalam relasi antar sesama adanya perilaku mencolok seseorang atau kelompok tertentu (suka menghalalkan segala cara, suka kekerasan) terhadap seseorang atau kelompok lain, maka perilaku tersebutlah yang direkam dan membentuk gambaran tentang orang lain. Ketika perilaku orang, kelompok tersebut dominan dilihat, dialami dan disaksikan oleh orang, kelompok lain, maka perilaku tersebut diidentifikasi sebagai nilai yang dianut kelompok lain.71 Identifikasi ini muncul atas kesadaran bahwa, masing-masing orang bersikap dan bertindak tidak terlepas dari pengetahuan yaitu sistem nilai-nilai yang dianutnya. Ketegangan relasi sosial dalam masyarakat majemuk disadari, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyadari apa yang dikehendaki seperti rasa aman, tenang, damai tidak tercapai; sebaliknya, kenyataan yang ada justru sebaliknya rasa cemas, teror dan kemarahan.72 Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pihak, bukan hanya berharap bisa mencapai apa yang dikehendakinya, melainkan juga telah mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkannya.73 Intinya, kekecewaan, ketidakpuasan muncul karena; kondisi tertentu (gembira, senang, puas) yang diharapkan terjadi dan telah mampu ditampilkan ternyata gagal dicapai (das Solen), dan sebaliknya kenyataan yang terjadi (das Sein) justru kondisi yang tidak diharapkan seperti perasaan cemas, teror dan ketidakpuasan.74 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kondisi ketegangan yang dialami merupakan energi penggerak yang bisa mendorong seseorang untuk mengatasi atau mengeluarkan diri dari 70 Tridayakisni, Psykologi Sosial Lintas Budaya, 174 – 175. Bart, Kelompok Etnik dan Batasannya, 19. 72 Pertemuan antar warga etnis yang berbeda juga pertemuan antar nilai yang dimiliki masing-masing, Bdk, Tridayakisni, Psykologi Sosial Lintas Budaya, 2. 73 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relative dan Kekerasan, 70-75. 74 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relative dan Kekerasan, 66. 71 25 kondisi yang tidak diharapkan dengan sekuat mungkin, bahkan dengan agresi-destruktif.75 Agresi-destruktif atau aksi-aksi penyerangan dengan kekerasan fisik akan diarahkan pada sumber-sumber penyebab; obyek, pihak lain, yang dianggap sebagai sumber penyebab munculnya kondisi ketegangan. Intinya, penyerangan secara fisik adalah salah satu cara yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melampiaskan energi ketegangan, kekecewaan dan kemarahan terhadap sumber penyebab.76 Namun, setelah penyerangan secara fisik dilakukan terhadap obyek, pihak lain yang dianggap penyebab munculnya kondisi yang tidak diinginkan, apa yang diharapkan (gembira, senang, puas) ternyata tidak juga terjadi; bahkan apa yang dihindari (cemas, teror, marah) semakin kompleks. Dalam konteks ini, melakukan kekerasan fisik sebagai upaya untuk menghilangkan atau memusnahkan sumber-sumber penyebab kegagalan untuk meraih apa yang diharapkan; sekaligus untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan, ternyata gagal. Oleh karena itu, pasca aksi kekerasan, jika salah satu atau kedua belah pihak tetap didorong oleh motivasi untuk mewujudkan kembali harapan untuk mengalami, melihat dan menyaksikan adanya rasa aman, tenang, gembira di satu sisi; dan harapan untuk bisa keluar dari kondisi tidak menyenangkan di sisi lain, maka perubahan harus dilakukan oleh semua pihak. Perubahan harus berpusat pada hakikat mendasar yaitu semua orang, kelompok selalu berharap agar sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan terjadi dan sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan bisa dihindari. Dalam konteks di atas, arah perubahan menjadi jelas yaitu seseorang, kelompok tertentu seharusnya tidak hanya menyadari bahwa dirinya sendiri, kelompok tertentu saja yang menghendaki rasa aman, tenang, damai, sebab harapan yang sama juga dikehendaki oleh 75 76 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relative dan Kekerasan, 65. Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 72. 26 orang, kelompok lain juga. Sebaliknya, jika seseorang, kelompok tertentu tidak menghendaki kondisi buruk terjadi pada dirinya, maka hal serupa juga tidak dikehendaki oleh orang, pihak lain pula. Nampak arah perubahan terletak pada bukan hanya menyadari harapan dan kehendak diri sendiri semata, melainkan juga menyadari bahwa harapan dan kehendak yang sama juga didambakan oleh orang, pihak lain pula. Dalam konteks inilah masing-masing pihak baru bisa menemukan “titik temu” yaitu semua orang pada hakikatnya memiliki harapan dan kehendak yang sama. Pada satu sisi sama-sama menghendaki adanya kegembiraan, kesenangan, dan kepuasan dan pada sisi lain berusaha menghindari situasi yang tidak dikehendaki (cemas, teror). Dalam konteks di atas, jelas harapan dan kehendak bersama tidak mungkin tercapai tanpa adanya partisipasi semua pihak yang terkait. Partisipasi tersebut paling tidak menyangkut beberapa hal, pertama: masing-masing pihak harus mengubah paradigmanya, dari semula hanya menyadari diri sendiri, kelompok tertentu saja, diubah menjadi menyadari orang dan kelompok lain pula. Artinya, jika pra konflik masing-masing pihak hanya mementingkan dan menyadari diri sendiri, kelompoknya semata, diubah terbuka dan mau menyadari orang, kelompok lain pula. Kedua, masing-masing pihak bukan hanya melemparkan kesalahan hanya pada pihak lain, tetapi juga terbuka dan mau untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri pula. Misalnya, mengoreksi standar nilai yang cocok dalam situasi dan kondisi tertentu, belum tentu selalu cocok dengan kondisi yang berbeda dan berubah.77 Ketiga, harapan dan kehendak yang semula hanya diarahkan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok tertentu saja, diubah diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian, harapan dan kehendak 77 Ted Robert Gurr, Deprivasi Relatif dan Kekerasan, 64. 27 mendasar yang didambakan semua orang, akan terwujud apabila melibatkan semua pihak, dilakukan oleh semua pihak, demi dan untuk semua pihak secara bersama-sama. H. Metodologi Untuk menjawab pertanyaan tesis dan hipotesis di atas, secara umum penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Langkah pertama studi literatur: buku-buku, artikel, jurnal, website yang berkaitan dengan topik. Hal tersebut mengingat adanya jarak waktu dari peristiwa konflik hingga penulisan. Langkah kedua, adalah penelitian lapangan yaitu turun langsung ke Sampit sebagai data pembanding. Adapun proses penulisan dan penelitian secara keseluruhan menggunakan metode lingkaran pastoral. Setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan lingkaran pastoral berusaha melihat masalah secara sistematis, namun kelemahannya ada kesan melihat permasalahan secara fragmatis (terpisahpisah). Untuk itu, dalam tahap demi tahap penulis berupaya untuk tidak terjebak dalam mekanisme kaku antara tahap satu dengan tahap lainnya. Untuk itu antara tahap satu dengan tahap lain bersifat terbuka dan fleksibel sehingga terjadinya korelasi yang dinamis dan kritis. Tujuannya adalah agar masalah yang diangkat tidak terjebak dalam mekanisme kaku seolah terpisah tahap satu dengan tahap lainnya, melainkan antara tahap-tahap dalam lingkaran pastoral ada hubungan yang sistematis, sinergis dan dinamis antara satu dengan lainnya. 28 (2) Analisis Sosial (3) Refleksi Teologis Pengalaman (1) Pemetaan Masalah (4) Perencanaan Pastoral 1. Pemetaan Masalah : Profil Daerah Sampit Dalam pemetaan masalah penulis akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi daerah Sampit, tempat kekerasan tahun 2001 berlangsung. Penggambaran mengenai keadan geografis, penduduk, diharapkan dapat memberi konteks secara fisik dalam hubungan dengan peristiwa kekerasan tahun 2001. Sampit adalah ibu kota dari kabupaten Kota waringin Timur yang luas wilayahnya 50.700 km2. Luas wilayah tersebut dihuni oleh kurang lebih 120.749 jiwa.78 Sebagaimana daerah lainnya, penduduk Sampit juga terdiri dari masyarakat yang majemuk suku dan budaya seperti suku Dayak, Madura, Banjar, Jawa, Cina dan lain sebagainya. Menurut Muchran Karno,79 dari populasi di atas, etnis Madura mencapai lebih dari 60% atau kurang lebih 56.000 jiwa atau jauh lebih besar dari warga etnis lain, termasuk Dayak. Dengan demikian, relasi antar warga yang berbeda suku dan budaya tidak bisa dihindari pula. Relasi sosial antar warga Dayak dengan warga Madura sudah terjadi sejak lama di 78 Edi Petebang, Amuk Sampit, (Pontianak, IDRD, 2001), 22. Muchran Karno, Kasi IPDS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, wawancara, tanggal, 17 Mei 2005. 79 29 Sampit. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, sudah ada warga Madura di Sampit. Menurut pengakuan tokoh Dayak, warga Madura pertama kali datang ke Sampit dimulai sejak dikirim oleh Belanda untuk bekerja pada pabrik Sawmil-kayu-Moulding milik swasta Belanda bernama N.V. Bruiynzeel Dajak Houtbedryven.80 Setelah Indonesia merdeka, pekerja Madura tetap menetap di Sampit. Selanjutnya kedatangan etnis Madura semakin bertambah sejak tahun 1950-1960 melalui transmigrasi spontan.81 Pertambahan pesat jumlah warga Madura juga terkait dengan kebiasaan mudik pada lebaran haji ke pulau Madura dan sekembalinya ke Sampit selalu membawa sanak saudara.82 Hasilnya adalah, beberapa kecamatan selain di ibukota Sampit, seperti Kota Besi, Samuda, Bajarum, mayoritas penduduknya adalah warga Madura. Selain warga Madura, juga ada warga Dayak dan warga lainya di Sampit. Walaupun suku Dayak merupakan suku asli di Sampit, tetapi sebagian besar warga etnis Dayak lebih memilih tinggal di hulu-hulu sungai, pedalaman, pegunungan. Warga Dayak yang tinggal di kota Sampit adalah warga Dayak yang tidak lagi menggantungkan hidup pada hutan, alam, seperti pegawai negeri, swasta. Warga Dayak yang berada di kota Sampit hanya sebagian kecil saja, misalnya warga Dayak yang menjadi anggota jemaat GKE tercatat 5. 677.83 Jumlah inilah yang bersentuhan dengan warga Madura pada saat konflik, termasuk dalam relasinya kembali dengan pengungsi Madura selanjutnya. Selama penelitian berlangsung,84 penulis menggali dan menelusuri akar kekerasan dan dampak kekerasan yang dirasakan oleh warga jemaat GKE yang berasal dari suku Dayak dan 80 Amu Linu (ed), Majelis Adat Dayak, 31. J. Patianom, dkk, Sejarah Sosial Palangka Raya, (Departemen P & K, Direkt Sejarah dan Nilai Tradisional proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1992), 4-5. 82 J. Patianom, dkk, Sejarah Sosial Palangka Raya, 5. 83 Data statistik Gereja Kalimantan Evangelis, Almanak Nast GKE tahun 2003, (Banjarmasin, MS-GKE, 2003) lampiran. 84 Penelitian berlangsung dari pertengahan Mei sampai pertengahan Juni 2005 di Sampit dan sekitarnya. 81 30 warga Madura yang baru saja kembali dari pengungsian yang saat ini telah berada di kota Sampit. Tahap ini, penulis mengajak warga jemaat untuk mengingat pengalaman relasinya dengan warga Madura; aspek apa saja yang mereka lihat, alami, dan saksikan tentang sikap, tindak-tanduk warga Madura dan sebaliknya. Kesulitan yang dialami penulis adalah mencari informasi dari warga Madura, sebab sebagian besar dari mereka masih tertutup dan tidak berani banyak bicara. Masih terlihat ekspresi ketakutan yang menyelimuti hampir semua pengungsi Madura, sehingga mereka sangat hati-hati untuk menerima tamu dan bicara. Metode yang digunakan adalah observasi partisipasi dengan pendekatan kualitatif.85. Adapun teknik penelitian yang dipakai adalah, pengamatan, dan wawancara. Dalam pengamatan, penulis melihat dan mengamati fakta dan data fisik seperti pengungsi Madura, kelompok warga Dayak, hiruk-pikuk kesibukan kedua belah pihak sehari-hari. Dalam pengamatan peneliti mengamati pergaulan antara Dayak dan Madura di pasar, terminal, tempat hiburan, dan sebagainya. Pengamatan terhadap warga Dayak, dilakukan dengan berkunjung dan memperhatikan pola pergaulan. Wawancara dilakukan untuk mendengar pengakuan langsung dari berbagai pihak yang terkait tentang apa yang mereka lihat, alami dan saksikan. Warga jemaat GKE Dayak yang menjadi informan adalah para pendeta GKE, Majelis jemaat, anggota jemaat tertentu terutama yang terlibat konflik atau yang menjadi korban, para tokoh Dewan Adat Dayak, tokoh pemuda gereja. Wawancara terhadap warga Madura diarahkan bagi para tokoh dan ulama Madura, misalnya H. Misland, beberapa warga Madura yang baru saja kembali dari pengungsian, seperti keluarga besar Ibu Gima, Suminah, dan Seruni. Kesulitan menemui warga Madura lainnya karena ada yang tidak berani mengakui secara terus-terang bahwa mereka adalah Madura. 85 Lexi Moeleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosdakarya,1997), 5-10. 31 2. Kerangka analisis: Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Dalam relasi sosial antar kelompok yang berbeda-beda, bukan hanya pertemuan antar orang, tetapi juga pertemuan antar nilai yang dianut.86 Positif (nir kekerasan) atau negatif (kekerasan) relasi yang dibangun sangat tergantung dari pesan pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain.87 Oleh karena itu, apapun bentuk sikap dan tindakan yang ditampilkan seseorang, kelompok lain terhadap orang, kelompok tertentu, akan mempengaruhi pengetahuannya terhadap orang, kelompok lain tersebut. Dalam memahami sikap dan tindakan kelompok lain, juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai yang dianutnya. Artinya, penilaian terhadap sikap dan tindakan pihak lain akan dipahami berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya. Sikap dan tindakan kelompok lain tersebut tidak akan dinilai sebagai kategori salah atau benar, apabila tidak adanya standar nilai yang dianutnya. Standar nilai tersebut bukan hanya membentuk pengetahuannya tetapi juga menjadi pedoman untuk menilai salah atau benarnya sikap dan tindakan pihak lain.88 Dalam konteks itu, apabila dalam relasi sosial, salah satu pihak menampilkan sikap dan tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pihak lain, maka akan memunculkan kesadaran telah terjadinya pertentangan. Pertentangan akan terjadi, apabila salah satu pihak menyadari bahwa, perilaku pihak lain tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai normatif yang dianutnya. Dengan kata lain, pertentangan disadari oleh salah satu pihak ketika apa yang seyogyanya atau seharusnya terjadi (das Solen) berbeda dengan kenyataan yang terjadi (das Sein). Dalam konteks itu, pertentangan atau kontras akan terjadi apabila: pertama, sikap dan tindakan kelompok tertentu memang nyata telah melanggar nilai-nilai yang dianut kelompok 86 Tridayakisni, dkk, Psikologi Lintas Budaya: Realitas Pertemuan Budaya, 2. Suwarsih, Warnaen, Stereotipe Etnis Dalam Masyarakat Multietnis, 79. 88 Bdk., Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya, ( Jakarta, UI-Press, 1988), 19. 87 32 lain. Kedua, pertentangan atau kontras disadari, akibat terjadinya pendangkalan pemahaman atas nilai-nilai yang dianut oleh pihak tertentu. Pendangkalan pemahaman bisa saja terjadi, apabila nilai-nilai yang dianut dipahami secara sempit hanya untuk mengokohkan kepentingan penganutnya saja.89 Pertentangan terjadi bisa juga disebabkan kombinasi yang pertama dan yang kedua di atas. Kesadaran adanya kontras antara apa yang seharusnya terjadi (das Solen) namun dalam kenyataan justru tidak terjadi (das Sein) akan melahirkan kekecewaan dan kemarahan bagi salah satu pihak yang merasa memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapannya90. Kekecewaan adalah ekspresi ketidakpuasan91 karena harapan tentang nilai-nilai normatif yang seharusnya dihargai, namun dalam kenyataan justru seolah-olah telah dilanggar. Kekecewaan tersebut akan meningkat menjadi kemarahan, ketika pihak tertentu menyadari penyebab kegagalan untuk mewujudkan harapan, diyakini akibat ulah dari pihak lain. Kekecewaan dan kemarahan merupakan “amunisi” yang siap meledak menjadi aksi-aksi perlawanan fisik secara destruktif92 terhadap pihak yang dianggap telah melanggar nilai-nilai normatif. Aksi-aksi perlawan fisik akan terjadi apabila adanya pemicu atau penyulut93 yang semakin memperjelas bahwa harapan pihak tertentu misalnya rasa aman, tenang, dan rukun tidak terwujud akibat ulah pihak lain. 89 Bdk., Hardjana, Konflik di Tempat Kerja, (Yogyakarta, Kanisius, 1994), 9. Bdk., Ted Robert Gurr, Deprivasi Relative dan Kekerasan, 62 –65. 91 Bdk., Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya, Kartika, 1997), 295. 92 Bdk., Erich Fromm, Akar Kekerasan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 82, Judul asli: The Anatomy of Human Destructiveness. 93 Riza Sihbudi, (ed), Kerusuhan Sosial di Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2001), 188. 90 33 3. Refleksi Teologis Dalam refleksi teologis, penulis akan menawarkan wacana tentang relasi positif antar sesama sebagai acuan relasi sosial pasca konflik. Refleksi teologis ini akan merujuk pada teks Lukas 10:25-37 sebagai dasar pijakan dan teks Lukas 6:12-42 sebagai pendukung. Adapun pendekatan yang akan ditempuh dalam refleksi teologis ini adalah pendekatan narasi. Setiap pendekatan ada kelemahan, begitu juga dalam tafsir narasi, dimana penafsir harus tunduk di bawah otoritas pengisah, padahal penafsir menghendaki makna narasi juga hidup bagi konteks penafsir pula. Oleh karena itu, pendekatan narasi hanya sebagai sarana untuk menemukan makna “relasi positif antar sesama’, kemudian penafsir merespon atau menghidupkan makna itu lebih dinamis sesuai dengan konteks penafsir pula. Tujuan yang diharapkan adalah, makna itu bukan hanya bermanfaat bagi pengisah, tetapi juga bermanfaat bagi pendengar atau penafsir, sesuai dengan konteks pergumulan yang dihadapinya. 4. Perencanaan Pastoral Wacana teologis menjadi pedoman bagi perubahan selanjutnya. Dalam rangka perubahan diperlukan media atau sarana untuk menjemaatkan pemikiran teologis. Salah satu sarana yang dapat dipakai dalam perubahan adalah pembangunan jemaat. Peran pembangunan jemaat adalah mengkongkretkan dari pemikiran teologis ke praksis. Peralihan dari teori ke praksis tidak akan terwujud tanpa adanya pemberdayaan. Oleh karena itu, peran pembangunan jemaat adalah peran pemberdayaan menuju perubahan yang transformatif. I. Sistematika Penulisan 34 Bab I : Pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, hipotesis, metode penulisan, kerangka teoritis, sistematika penulisan. Bab II : Pemetaan masalah. Pemetaan masalah diarahkan pada fakta kerusakan relasi sosial baik secara umum di maupun secara khusus kekerasan tahun 2001 di Sampit. Bab III : Analisis Sosial: Analisis sosial akan mengacu pada kerangka teori-teori sosial yang dibangun. Analisis sosial diarahkan pada relasi sosial. Tiga aspek penting dalam berelasi yaitu: pengetahuan, sikap dan tindakan akan menjadi sasaran pengkajian. Bab IV : Refleksi Teologis. Refleksi teologis ini bersumber dari teks Alkitab (Lukas 10: 2537; Lukas 6:12-42) tentang relasi positif antar sesama. Refleksi teologis merupakan dasar bagi wacana perubahan dalam relasi sosial selanjutnya. Perubahan tanpa dasar dan patokan yang jelas akan menghasilkan perubahan ekstrim dan konfrontatif. Dengan demikian, pemikiran teologis menjadi kunci utama dalam menentukan arah perubahan yang hendak diwujudkan. Perubahan yang hendak diwujudkan adalah perubahan yang transformatif. Bab V : Perencanaan Pastoral: Dalam perencanaan pastoral akan dipaparkan bagaimana proses perubahan bisa diwujudkan. Dalam bab ini berisi sejumlah rekomendasi, usulan, dan saran bagi pembangunan jemaat. 35