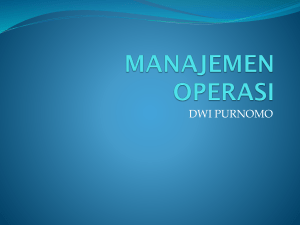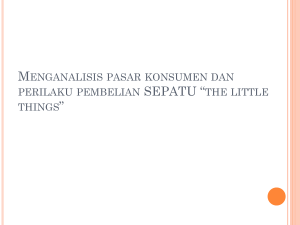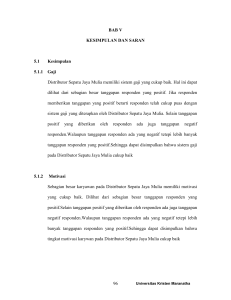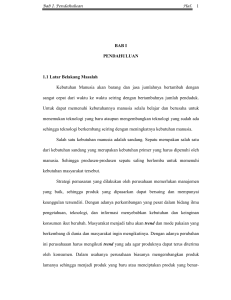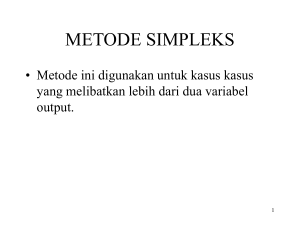Sepatu Orang Lain
advertisement
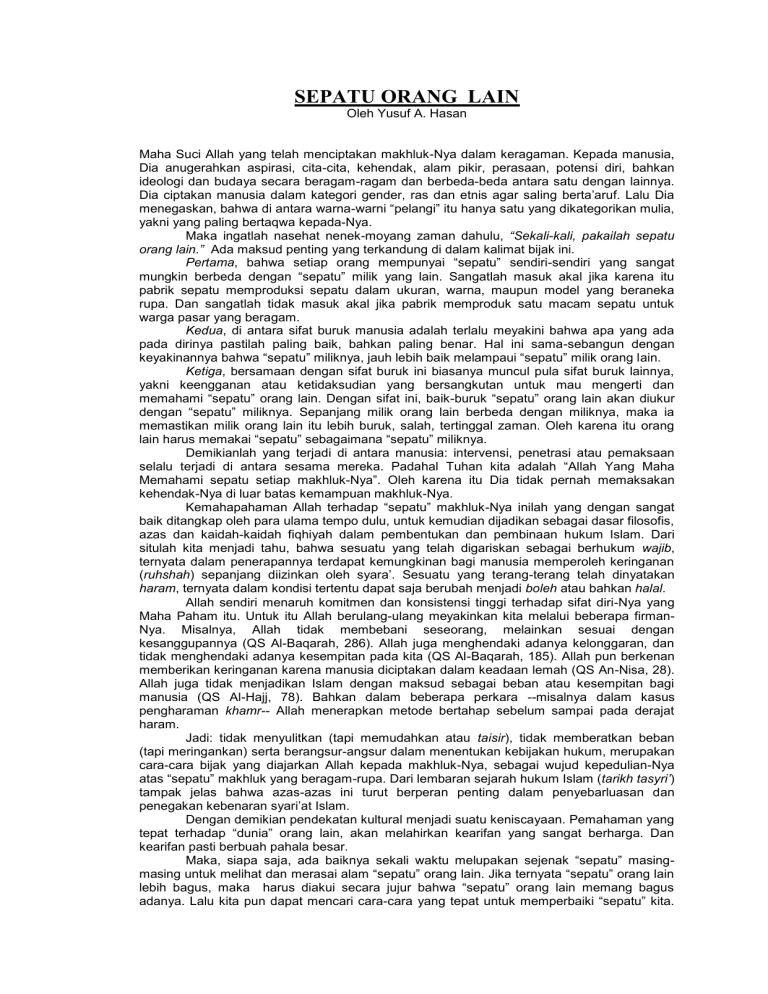
SEPATU ORANG LAIN Oleh Yusuf A. Hasan Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk-Nya dalam keragaman. Kepada manusia, Dia anugerahkan aspirasi, cita-cita, kehendak, alam pikir, perasaan, potensi diri, bahkan ideologi dan budaya secara beragam-ragam dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dia ciptakan manusia dalam kategori gender, ras dan etnis agar saling berta’aruf. Lalu Dia menegaskan, bahwa di antara warna-warni “pelangi” itu hanya satu yang dikategorikan mulia, yakni yang paling bertaqwa kepada-Nya. Maka ingatlah nasehat nenek-moyang zaman dahulu, “Sekali-kali, pakailah sepatu orang lain.” Ada maksud penting yang terkandung di dalam kalimat bijak ini. Pertama, bahwa setiap orang mempunyai “sepatu” sendiri-sendiri yang sangat mungkin berbeda dengan “sepatu” milik yang lain. Sangatlah masuk akal jika karena itu pabrik sepatu memproduksi sepatu dalam ukuran, warna, maupun model yang beraneka rupa. Dan sangatlah tidak masuk akal jika pabrik memproduk satu macam sepatu untuk warga pasar yang beragam. Kedua, di antara sifat buruk manusia adalah terlalu meyakini bahwa apa yang ada pada dirinya pastilah paling baik, bahkan paling benar. Hal ini sama-sebangun dengan keyakinannya bahwa “sepatu” miliknya, jauh lebih baik melampaui “sepatu” milik orang lain. Ketiga, bersamaan dengan sifat buruk ini biasanya muncul pula sifat buruk lainnya, yakni keengganan atau ketidaksudian yang bersangkutan untuk mau mengerti dan memahami “sepatu” orang lain. Dengan sifat ini, baik-buruk “sepatu” orang lain akan diukur dengan “sepatu” miliknya. Sepanjang milik orang lain berbeda dengan miliknya, maka ia memastikan milik orang lain itu lebih buruk, salah, tertinggal zaman. Oleh karena itu orang lain harus memakai “sepatu” sebagaimana “sepatu” miliknya. Demikianlah yang terjadi di antara manusia: intervensi, penetrasi atau pemaksaan selalu terjadi di antara sesama mereka. Padahal Tuhan kita adalah “Allah Yang Maha Memahami sepatu setiap makhluk-Nya”. Oleh karena itu Dia tidak pernah memaksakan kehendak-Nya di luar batas kemampuan makhluk-Nya. Kemahapahaman Allah terhadap “sepatu” makhluk-Nya inilah yang dengan sangat baik ditangkap oleh para ulama tempo dulu, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis, azas dan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam pembentukan dan pembinaan hukum Islam. Dari situlah kita menjadi tahu, bahwa sesuatu yang telah digariskan sebagai berhukum wajib, ternyata dalam penerapannya terdapat kemungkinan bagi manusia memperoleh keringanan (ruhshah) sepanjang diizinkan oleh syara’. Sesuatu yang terang-terang telah dinyatakan haram, ternyata dalam kondisi tertentu dapat saja berubah menjadi boleh atau bahkan halal. Allah sendiri menaruh komitmen dan konsistensi tinggi terhadap sifat diri-Nya yang Maha Paham itu. Untuk itu Allah berulang-ulang meyakinkan kita melalui beberapa firmanNya. Misalnya, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al-Baqarah, 286). Allah juga menghendaki adanya kelonggaran, dan tidak menghendaki adanya kesempitan pada kita (QS Al-Baqarah, 185). Allah pun berkenan memberikan keringanan karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS An-Nisa, 28). Allah juga tidak menjadikan Islam dengan maksud sebagai beban atau kesempitan bagi manusia (QS Al-Hajj, 78). Bahkan dalam beberapa perkara --misalnya dalam kasus pengharaman khamr-- Allah menerapkan metode bertahap sebelum sampai pada derajat haram. Jadi: tidak menyulitkan (tapi memudahkan atau taisir), tidak memberatkan beban (tapi meringankan) serta berangsur-angsur dalam menentukan kebijakan hukum, merupakan cara-cara bijak yang diajarkan Allah kepada makhluk-Nya, sebagai wujud kepedulian-Nya atas “sepatu” makhluk yang beragam-rupa. Dari lembaran sejarah hukum Islam (tarikh tasyri’) tampak jelas bahwa azas-azas ini turut berperan penting dalam penyebarluasan dan penegakan kebenaran syari’at Islam. Dengan demikian pendekatan kultural menjadi suatu keniscayaan. Pemahaman yang tepat terhadap “dunia” orang lain, akan melahirkan kearifan yang sangat berharga. Dan kearifan pasti berbuah pahala besar. Maka, siapa saja, ada baiknya sekali waktu melupakan sejenak “sepatu” masingmasing untuk melihat dan merasai alam “sepatu” orang lain. Jika ternyata “sepatu” orang lain lebih bagus, maka harus diakui secara jujur bahwa “sepatu” orang lain memang bagus adanya. Lalu kita pun dapat mencari cara-cara yang tepat untuk memperbaiki “sepatu” kita. Jika milik kita ternyata lebih baik, maka kita pun terjauh dari sifat takabur, tetapi terus berusaha mencari strategi dan cara yang benar dan tepat agar “sepatu” milik orang menjadi baik sebagaimana kepunyaan kita. Sumber: Suara Muhammadiyah Edisi 17-02