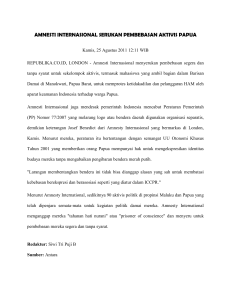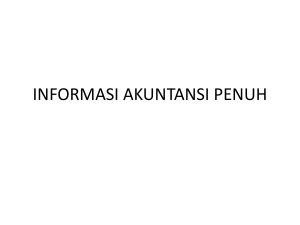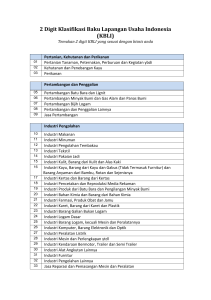pernyataan tertulis ictj: keabsahan dari komisi kebenaran dan
advertisement
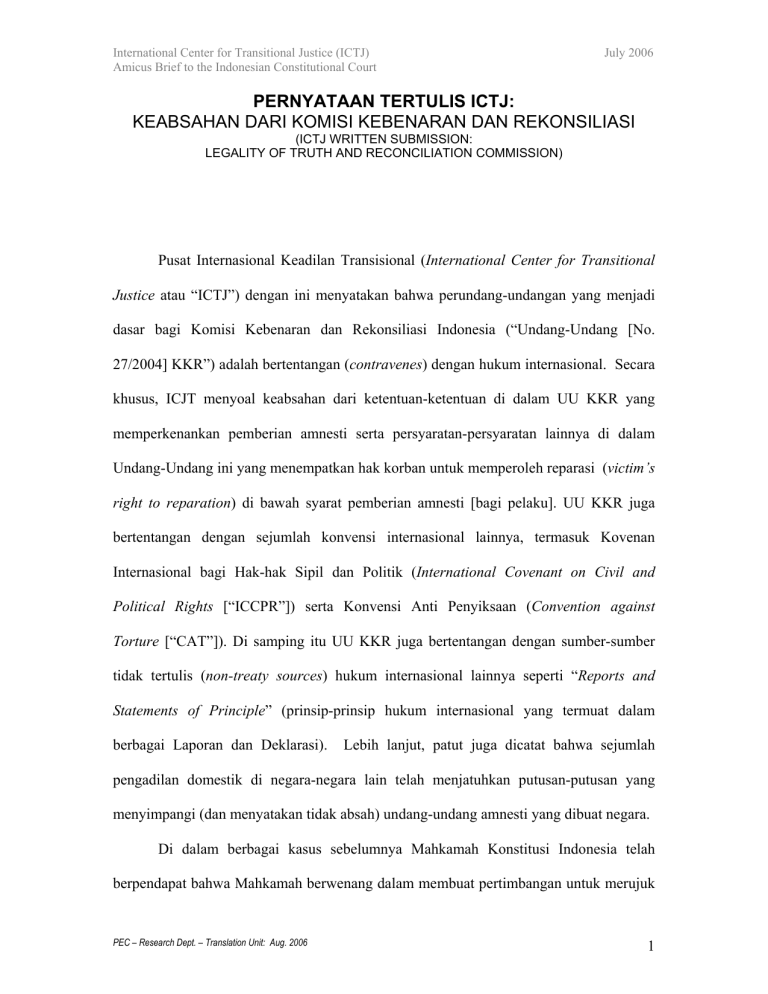
International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 PERNYATAAN TERTULIS ICTJ: KEABSAHAN DARI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (ICTJ WRITTEN SUBMISSION: LEGALITY OF TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION) Pusat Internasional Keadilan Transisional (International Center for Transitional Justice atau “ICTJ”) dengan ini menyatakan bahwa perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia (“Undang-Undang [No. 27/2004] KKR”) adalah bertentangan (contravenes) dengan hukum internasional. Secara khusus, ICJT menyoal keabsahan dari ketentuan-ketentuan di dalam UU KKR yang memperkenankan pemberian amnesti serta persyaratan-persyaratan lainnya di dalam Undang-Undang ini yang menempatkan hak korban untuk memperoleh reparasi (victim’s right to reparation) di bawah syarat pemberian amnesti [bagi pelaku]. UU KKR juga bertentangan dengan sejumlah konvensi internasional lainnya, termasuk Kovenan Internasional bagi Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights [“ICCPR”]) serta Konvensi Anti Penyiksaan (Convention against Torture [“CAT”]). Di samping itu UU KKR juga bertentangan dengan sumber-sumber tidak tertulis (non-treaty sources) hukum internasional lainnya seperti “Reports and Statements of Principle” (prinsip-prinsip hukum internasional yang termuat dalam berbagai Laporan dan Deklarasi). Lebih lanjut, patut juga dicatat bahwa sejumlah pengadilan domestik di negara-negara lain telah menjatuhkan putusan-putusan yang menyimpangi (dan menyatakan tidak absah) undang-undang amnesti yang dibuat negara. Di dalam berbagai kasus sebelumnya Mahkamah Konstitusi Indonesia telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang dalam membuat pertimbangan untuk merujuk PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 1 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 dan melandaskan diri pada hukum internasional, termasuk pada perjanjian-perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga pada deklarasi-deklarasi yang tidak mengikat. Di dalam kasus mengenai Pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah ini merujuk sekaligus kepada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) (yang sesungguhnya belum diratifikasi, namun kemudian Indonesia kemudian melakukan aksesi [acceded] terhadapnya) sebagai sumber-sumber rujukan hukum cukup penting (persuasive sources).1 Mahkamah Konstitusi secara spesifik merujuk pada larangan yang terkandung di dalam Deklarasi Universal HAM atas berbagai bentuk diskriminasi, dalam rangka mendukung pertimbangannya perihal penafsiran atas ketentuan Pasal 28D(1) dan 28I(2) Undang-Undang Dasar Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan ICCPR dan mengutip sejumlah ketentuan dari ICCPR ini, berkenaan dengan kesetaraan di hadapan hukum dan larangan atas diskriminasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa Mahkamah Konstitusi Indoneisa dalam sejumlah kasus yang diperiksanya telah merujuk kepada aspek-aspek hukum internasional, yang pada prinsipnya belum diinkorporasikan ke dalam hukum nasional, dan menggunakannya sebagai sumber hukum dalam rangka mencapai keputusan tentang keabsahan aspek-aspek hukum nasional (domestic law). Sebagai tambahan, Dewan Perwakilan Rakyat [Indonesia] telah mengesahkan bahwa perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi harus dianggap sebagai hukum yang mengikat di tataran nasional (binding in domestic law). Undang-Undang Keputusan Mahkamah Konstitusional, Kasus No. 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004. Keputusan mengenai Pasal 60g Undang-Undang No.12/2003. 1 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 2 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Nomor 39/1999 mengenai Hak-hak Asasi Manusia merupakan sebuah Undang-Undang yang mengadopsi statutory bill of rights yang komprehensif. Undang-Undang ini melengkapi perlindungan dan penghormatan atas hak asasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal 7 tertulis: (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Pasal 7 ini saling melengkapi dengan pasal 71—masih di dalam UU yang sama—yang menyatakan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Maka secara bersama-sama, pasal 7 dan 71 dari UndangUndang Nomor 39/1999, mewajibkan pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan mempromosikan hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalam Undang-Undang ini maupun di dalam hukum internasional. Perlindungan serta promosi tersebut mencakup tindakan-tindakan positif (positive measures) berupa penyelidikan, penuntutan serta penyediaan reparasi atas pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi oleh UndangUndang tersebut. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 39/1999 ini secara tegas menyatakan bahwa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia harus dianggap sebagai hukum positif yang mengikat dalam tataran nasional/domestik (treaties ratified by Indonesia are binding in domestic law). Penting pula diingat bahwa Indonesia bukan sekadar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa—selaku Negara Pihak serta bekerjasama dengan PBB di dalam promosi PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 3 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 atas HAM tersebut,2—namun Indonesia juga adalah anggota Dewan HAM PBB. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban tambahan untuk memenuhi “standar tertinggi” perlindungan hak-hak asasi manusia.3 Adalah berlandaskan pertimbangan ini di dalam benak kita, maka kami melanjutkan uraian mengenai status Undang-Undang KKR di hadapan hukum internasional. Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945 berlaku secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945. Pasal 55 (c) menyatakan bahwa PBB “akan mempromosikan penghargaan universal bagi—dan mengawasi HAM serta hak-hak fundamental lainya tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau pun agama”. Sementara pasal 56 Piagam PBB “Segenap Negara pihak berjanji untuk untuk mengemban tindakan secara bersamasama maupun mandiri” dengan PBB untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada Pasal 55. 2 Para anggota Dewan HAM PBB “seharusnya menjunjung tinggi standar tertinggi dalam promosi dan perlindungan atas HAM…dan [hal ini] akan ditinjau…selama masa keanggotaannya” “menjunjung standar tertinggi dalam mempromosikan dan melindungi HAM…dan untuk ditinjau…selama rentang masa keanggotaan mereka…”. Resolusi Majelis Umum Res. 60/251, 15 Maret 2006, UN Doc. A/RES/60/251, 3 April 2006, alinea 9. 3 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 4 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court I July 2006 UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL A Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (“ICCPR”)4 ICTJ menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan UU KKR yang membuka kemungkinan pemberian amnesti dan yang mengharuskan pemberian reparasi di bawah syarat pemberian amnesti [bagi pelaku] adalah bertentangan dengan Pasal 2(3), 6(1), 7, 9(5) dan 14(6) ICCPR. Pada tanggal 23 Februari 2006 Indonesia telah mengaksesi (acceded) ICCPR. Dalam pernyataan ini kami memfokuskan diri pada pertentangan atau pelanggaran-pelanggaran pasal 2(3), 6(1) dan 7 ICCPR yang merupakan pasal-pasal yang paling relevan dalam permasalahan ini. Betapapun, perlu dicatat bahwa terdapat pula argumen-argumen kuat untuk mendukung dalil (proposition) bahwa UU KKR bertentangan dengan Pasal 9(5) dan 14(6) ICCPR. Misalnya saja, menyadari bahwa di dalam Komentar Umum (General Comment) Nomor 21, Komite HAM PBB (HRC) menyatakan bahwa “orang-orang yang ditangkap dan ditahan [seharusnya] memiliki akses…untuk mendapatkan kompensasi yang pantas, jika ternyata mengalami pelanggaran [atas hak-haknya],”5 adalah logis jika kita menyimpulkan bahwa Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan Pasal 9(5) ICCPR yang memberikan hak atas kompensasi bagi para korban penangkapan atau pun penahanan sewenang-wenang. Serupa pula halnya dengan Pasal 14(6) ICCPR yang menetapkan bahwa siapa pun memiliki hak atas kompensasi ketika vonis pidananya dibatalkan dikarenakan telah terjadi kekeliruan 4 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171. Komentar Umum ICCPR No. 21 (Sesi 44, 1992): Pasal 10: menggantikan Komentar Umum 9 berkenaan dengan Perlakuan Manusiawi atas Orang-orang yang Dicabut Kebebasannya (Humane Treatment of Persons Deprived of Liberty), A/47/40 (1992) 195 pada alinea 7. 5 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 5 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 hukum (where there has been a miscarriage of justice). Sekali lagi, adalah logis jika disimpulkan bahwa Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan Pasal 14(6). 1. Pasal 2(3) ICCPR Pasal 2(3) ICCPR menyatakan bahwa: Setiap Negara Pihak dari Kovenan ini berkewajiban: (a) menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif (effective remedy), walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara; (b) menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; (c) menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Jelaslah bahwa Pasal 27 UU KKR melanggar Pasal 2(3) ICCPR. Pasal 27 UU KKR sendiri menyatakan: “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Penjelasan resmi dari UU KKR ini sendiri menyatakan bahwa: “Apabila permohonan amnesti ditolak maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh Negara, serta perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”. Patut dicatat pula bahwa dalam hal ini tidak ada jaminan bahwa Pengadilan HAM akan memproses kasus yang permohonan amnestinya telah ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan pula bahwa seorang korban pelanggaran HAM akan memperoleh kompensasi yang merupakan haknya. Dengan menempatkan pemberian kompesasi secara bersyarat (tergantung) pada pemberian amnesti, maka Pasal 27 menyalahi hak atas pemulihan efektif (effective PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 6 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 remedy), yang telah ditetapkan oleh Komite HAM PBB (“Human Rights Committee” selanjutnya disebut sebagai “HRC” saja) sebagai hak yang harus diberikan tanpa syarat (unconditional right). (a) Komentar-Komentar Umum Di dalam Komentar Umum (General Comment) No. 31 HRC menegaskan arti penting hak atas pemulihan efektif serta mendefinisikan bahwa hak ini mencakup hak untuk memperoleh kompensasi yang patut. HRC menetapkan bahwa Pasal 2(3) mensyaratkan bahwa Negara-Negara Pihak memberikan reparasi pada orang-orang yang hak sipil dan politiknya telah dilanggar. Tanpa pemberian reparasi bagi orang-orang tersebut, maka kewajiban untuk menyediakan pemulihan efektif tidak dapat diwujudkan... Komite HAM memandang bahwa pada umumnya [ketentuan-ketentuan] Kovenan berimplikasi pada pemberian kompensasi yang patut”.6 Adalah jelas bahwa individu-individu yang akan memberikan keterangan di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah mereka yang hak-hak sipil dan politiknya telah dilanggar. Sebagai konsekuensinya orang-orang ini juga memiliki hak atas reparasi, terlepas apakah amnesti akan diberikan [kepada pelaku] atau tidak. (b) Catatan Penutup Di dalam Catatan Penutup atas El Salvador, HRC menyatakan peraturan mengenai Amnesti: “telah menyalahi hak atas pemberian pemulihan efektif sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 Kovenan. Karena pengaturan ini mencegah investigasi serta penghukuman atas semua yang bertanggungjawab atas ke HAM serta memberikan Komentar Umum ICCPR No. 31 [80] mengenai Hakikat Kewajiban Hukum Umum yang ditetapkan atas Negara-negara Pihak Kovenan, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. (2004), alinea 16. 6 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 7 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 kompensasi bagi para korban mereka”.7 Tidak jauh berbeda, di dalam Catatan Penutupnya atas Peru, HRC menemukan bahwa “…pemberian amnesti mencegah penyelidikan serta hukuman yang patut atas para pelaku pelanggaran HAM masa lalu… dan oleh karenanya melanggar pula pasal 2 Kovenan. …Pemerintah didesak untuk menegakkan suatu sistem kompensasi yang efektif bagi para korban pelanggaran HAM”.8 Di tahun 2000, HRC menyertakan rekomendasi berikut ini di dalam Catatan Penutup atas Argentina: “Pelanggaran hak-hak sipil dan politik selama kekuasaan militer seharusnya tetap dapat dituntut (should be prosecutable) selama mungkin, dengan keberlakuan (applicability) sejauh mungkin sampai pada waktu yang diperlukan untuk menghadapkan para pelakunya ke hadapan hukum. Komite merekomendasikan agar upaya-upaya tegas tetap dilanjutkan atas persoalan ini”.9 (c) Yurisprudensi HRC telah menyampaikan berbagai keputusan untuk menegaskan Pasal 2(3) ICCPR bahwa para korban pelanggaran ICCPR mendapatkan kompensasi yang patut. Dalam kasus Cagas vs. Filipina HRC menemukan bahwa pemerintah Filipina telah melanggar Pasal 9 dan 14 of ICCPR, berdasarkan kenyataan bahwa para penulis telah ditahan lebih dari empat tahun tanpa pengadilan. HRC memutuskan bahwa sesuai dengan Pasal 2(3)(a) maka “Negara pihak berada di bawah kewajiban untuk memberikan HRC, Concluding Observations (Catatan Penutup) on El Salvador, UN. Doc. A/58/40 Vol. I (2003) 61, alinea 84(6). 7 8 HRC, Concluding Observations on Peru, UN. Doc. A/51/40 Vol. I (1996) 48, alinea 347, 358. 9 HRC, Concluding Observations on Argentina, UN. Doc. CCPR/CO/70/ARG (2000), alinea 9. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 8 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 para penulis dengan reparasi yang efekfif, yang akan mencakup kompensasi efektif atas waktu yang telah mereka habiskan secara tidak sah di dalam tahanan”.10 Di dalam kasus Brok vs. Republik Ceko, Robert Brok, seorang Yahudi yang hak milik keluarganya telah disita selama Perang Dunia II, mengajukan permasalahan ini ke hadapan HRC. Brok mengklaim bahwa Negara telah melanggar haknya untuk memperoleh kesetaraan hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum karena Negara menolak mengembalikan hak miliknya yang pernah disita. Dalam kenyataannya HRC memang menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran ICCPR dan bahwa hak atas pemulihan yang efektif dalam hal ini meliputi “restitusi atas hak milik atau kompensasi dan kompensasi yang patut atas periode selama Brok dan jandanya mengalami penyitaan hak milik”.11 Di dalam kasus Ashby vs. Trinidad and Tobago, Negara berketetapan untuk mengeksekusi Ashby sungguh pun HRC (Komite HAM) telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi sampai HRC sendiri rampung dalam membuat putusan final atas kasus ini. HRC menyampaikan pandangannya bahwa pengabaian atas permohonan HRC seperti itu sama saja artinya dengan menentang ICCPR. Oleh karena itu HRC berketetapan bahwa menurut Pasal 2(3) “Pertama-tama dan yang terutama Mr. Ashby seharusnya mendapatkan pemulihan efektif termasuk kesinambungan kehidupannya. Kompensasi yang patut juga harus diberikan kepada keluarganya yang masih hidup”.12 10 Cagas vs. Filipina, CCPR/C/73/D/788/1997. alinea 9. 11 Brok vs. Republik Ceko, CCPR/C/73/D/774/1997, alinea 9. 12 Ashby vs. Trinidad dan Tobago, CCPR/C/74/D/580/1994, alinea 12. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 9 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Di dalam kasus Lantsova vs. Federasi Rusia HRC mendapati bahwa Negara telah melanggar Pasal 6(1) ICCPR berkenaan dengan fakta mengenai bahwa kondisi yang amat buruk dari penjara Rusia telah mengakibatkan tewasnya sang narapidana. Oleh karena itu HRC memutuskan bahwa istri almarhum berhak atas kompensasi yang patut.13 Agak mirip pula, di dalam kasus Francis dkk. vs. Trinidad and Tobago HRC mendapati bahwa kondisi penjara yang amat tercela telah sekaligus melanggar hak-hak Francis dkk. (the authors), hak untuk “diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan atas martabat yang melekat pada individu manusia”. Oleh Karena itu HRC mendapati bahwa Francis dkk. berhak atas pemulihan efektif (effective remedy), termasuk kompensasi yang sewajarnya.14 Di dalam kasus Bondarenko vs. Belarus, pihak pengaju kasus mengklaim bahwa Negara telah melanggar ICCPR karena tidak menjalankan kewajibannya untuk memberitahukan sang orangtua (Bondarenko) atas putusan eksekusi mati terhadap putranya. HRC mendapati bahwa: kerahasiaan penuh yang melingkupi hari/tanggal eksekusi, maupun lokasi penguburan serta penolakan untuk menyerahterimakan jenazah untuk penguburan, memiliki efek pengintimidasian atau penghukuman pihak keluarga dengan membiarkan mereka secara sengaja berada di dalam kondisi tanpa kepastian dan tekanan mental. Komite (HRC) menganggap bahwa pelanggaran awal pihak otoritas dengan tidak memberitahukan pihak terkait perihal jadwal eksekusi mati putranya, serta tindakan lanjutan dengan tidak memberitahukan lokasi kuburan putranya tersebut, terakumulasi menjadi praktik tidak manusiawi terhadap pihak penggugat, yang merupakan pelanggaran atas Pasal 7 Kovenan…Sesuai dengan Pasal 2, alinea 3 (a) Kovenan, pihak Negara Pihak berada di bawah kewajiban untuk memberikan pemulihan efektif (effective remedy) bagi pihak pengadu, termasuk keharusan untuk memberitahukan lokasi kuburan putranya serta 13 Lantsova vs. Federasi Rusia, CCPR/C/74/763/1997, alinea 11. 14 Francis dkk. vs. Trinidad dan Tobago, CCPR/C/75/D/899/1999, alinea 5.7 – 7. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 10 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 kompensasi atas penderitaan yang telah dialaminya. Negara Pihak juga berada di bawah kewajiban untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.15 Keputusan-keputusan HRC di muka hanyalah sedikit contoh dari sekian banyak keputusan yang telah ditetapkan HRC untuk memastikan bahwa hak atas kompensasi adalah inheren (melekat) di dalam hak atas pemulihan efektif yang dijamin di dalam Pasal 2(3) ICCPR. Adalah jelas bahwa dengan menempatkan hak atas kompensasi sebagai sesuatu yang bersyarat dengan keharusan memberikan amnesti dan bukannya diberikan otomatis ketika pelanggaran tersebut terjadi, Indonesia melakukan pelanggaran atas kewajibannya sendiri di bawah Pasal 2(3) ICCPR. 2. Pasal 6(1) ICCPR Pasal 6(1) ICCPR menyatakan bahwa: “Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Telah dinyatakan secara resmi sebelumnya bahwa baik Pasal 1(9) maupun Pasal 27 Undang-Undang KKR bertentangan dengan Pasal 6(1) ICCPR. (a) Pasal 1(9) Undang-Undang KKR Pasal 1(9) Undang-Undang KKR menyatakan bahwa “amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [sic]”. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa Pasal 1(9) Undang-Undang KKR bertentangan dengan 6(1) ICCPR, berdasarkan ketentuan Pasal 6(1) ICCPR yang mewajibkan para pelaku pelanggaran HAM untuk dihadapkan ke pengadilan. 15 Bondarenko vs. Belarus, CCPR/C/77/D/886/1999, alinea 10.2 dan 12. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 11 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court (i) July 2006 Komentar Umum Di dalam Komentar Umum 6 mengenai implementasi dari Pasal 6 ICCPR, HRC menyatakan bahwa “Negara pihak seharusnya mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum pencabutan nyawa melalui tindakan-tindakan kriminal, namun juga mencegah pembunuhan oleh aparat keamanannya sendiri”.16 Pemberian amnesti sesuai dengan Pasal 1(9) Undang-Undang KKR mencegah penghukuman terhadap mereka yang telah terlibat di dalam pencabutan nyawa melalui tindakantindakan kriminal dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 6(1) ICCPR. (ii) Catatan Penutup Di dalam Catatan Penutup tahun 1993 atas Senegal HRC menyatakan bahwa “[k]eprihatinana khusus disampaikan atas kekuatiran bahwa Undang-Undang Amnesti akan dapat dipakai untuk memberikan impunitas bagi para pejabat Negara yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang seharusnya telah dihadapkan ke pengadilan”.17 Di dalam Catatan Penutup tahun 1993 atas Nigeria, HRC telah bersikukuh bahwa para agen Negara yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran HAM haruslah dihukum dan seharusnya “dengan alasan apa pun tidak boleh menikmati kekebalan lewat Undang-Undang Amnesti”.18 Serupa dengan hal ini, pada Catatan Penutup tahun 2002 atas Togo, HRC mencatat dengan penuh ketidaksetujuan bahwa “penerimaan atas perundangan seperti Undang-Undang Amnesti (Amnesty Act) hanya akan menegakkan ICCPR Komentar Umum 6 (Sesi Ke-16, 1982): Pasal 6: Hak atas Kehidupan [The Right to Life], A/37/40 (1982) 93, alinea 3. 16 17 HRC, Concluding Observations on Senegal, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 23, alinea 103. 18 HRC, Concluding Observations on Niger, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 88, alinea 425. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 12 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 budaya impunitas di Togo”.19 Nyatanya, terdapat begitu banyak contoh kasus ketika HRC—di dalam Catatan Penutupnya—telah menyampaikan pandangan bahwa pemberian amnesti dapat dilihat sebagai pelanggaran atas hak atas kehidupan yang dijamin di dalam Pasal 6(1) ICCPR. (iii) Yurisprudensi Yurisprudensi HRC adalah jelas di dalam pandangannya bahwa mereka yang melanggar Pasal 6(1) ICCPR haruslah dihadapkan ke pengadilan. Kesimpulan logis dari pandangan ini adalah karena amnesti melanggar 6(1) ICCPR. Sebagai contoh, misalnya pada kasus Barbato vs. Uruguay,20 HRC berpandangan bahwa Uruguay berada di bawah kewajiban untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk menyeret siapa pun yang didapati bertanggungjawab atas kematian Hugo Dermit. HRC mencapai kesimpulan sama pada kasus Barboeram dkk. vs. Suriname21 dan kasus Miango vs. Zaire.22 Di dalam kasus José Vicente dkk. vs. Columbia HRC menyatakan bahwa “Negera Pihak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara menyeluruh tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya atas penghilangan paksa serta pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kehidupan; dan agar melancarkan tuntutan pidana, mengadili serta menghukum mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.”23 19 HRC, Concluding Observations on Togo, UN. Doc. A/58/40 Vol. I (2002) 36, alinea 77(9). 20 Barbato vs. Uruguay, CCPR/C/17/D/84/1981. 21 Baboeram dkk. vs. Suriname, CCPR/C/24/D/148/1983. 22 Miango vs. Zaire, CCPR/C/31/D/194/1985. 23 José Vicente dkk. vs. Columbia, CCPR/C/60/D/612/1995. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 13 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court (b) July 2006 Pasal 27 Undang-Undang KKR Sebagimana dinyatakan di atas, Pasal 27 Undang-Undang KKR menyebutkan bahwa: “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Telah diyatakan bahwa Pasal 27 Undang-Undang KKR bertentangan dengan Pasal 6(1) ICCPR karena berbasiskan pada interprestasi Pasal 6(1) ICCPR yang mengharuskan para korban pelanggaran HAM mendapatkan kompensasi (yang tidak boleh diberikan secara bersyarat demi pemberian amnesti). (i) Catatan Penutup Di dalam sekian banyak Catatan Penutupnya HRC telah mendapati bahwa keharusan korban maupun keluarga mereka untuk memperoleh kompensasi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang diderita mereka berada di dalam cakupan Pasal 6(1) ICCPR. Di dalam Catatan Penutup tahun 2002 atas Mesir, HRC menyimpulkan bahwa “Negara seharusnya memastikan bahwa semua pelanggaran atas Pasal 6 dan 7 Kovenan diselidiki, serta—bergantung pada hasil investigasi tersebut—harus mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggungjawab dan memberikan reparasi kepada para korbannya. 24 HRC telah menegaskan bahwa para korban penyiksaan harus menerima kompensasi.25 HRC juga telah memutuskan bahwa para keluarga korban pembunuhan ekstra-yudisial harus menerima kompensasi.26 Lebih jauh lagi, HRC telah menyatakan 24 HRC, Concluding Observations on Egypt, UN. Doc. A/58/40 Vol. I (2002) 31, alinea 77(13). Lihat misalnya: HRC, Concluding Observations on Niger, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 88, alinea 425; HRC, Concluding Observations on Cameroon, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 36, alinea 203; HRC, Concluding Observations on Togo, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 44, alinea 250. 25 Lihat misalnya: HRC, Concluding Observations on Niger, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 88, alinea 425; HRC, Concluding Observations on Mexico, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 33, alinea 172; HRC, Concluding 26 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 14 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 bahwa kompensasi seharusnya diberikan bagi kasus-kasus penghilangan paksa.27 Kesimpulan yang sama telah diterapkan bagi para korban penahanan paksa;28 pemerkosaan;29 penggunaan kekerasan yang tidak patut oleh pihak kepolisian30 dan pelanggaran HAM lainnya. (ii) Yurisprudensi Di dalam kasus Barbato vs. Uruguay31 HRC berpandangan bahwa Negara pihak berada di bawah kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi yang patut kepada keluarga Barbato atas kematian ketika ia berada di dalam penahanan. Di dalam kasus Barboeram dkk. vs. Suriname32 HRC menyimpulkan bahwa Suriname diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada para keluarga dari orang-orang yang dibunuh oleh pihak polisi militer. HRC mencapai kesimpulan serupa di dalam kasus Miango vs. Zaire33 yang pada pokoknya merupkan kasus penyiksaan seseorang sampai mati oleh anggota-anggota angkatan bersenjata. Observations on Cameroon, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 36, alinea 203; HRC, Concluding Observations on Togo, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 44, alinea 250. Lihat misalnya: HRC, Concluding Observations on Mexico, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 33, alinea 172; HRC, Concluding Observations on Togo, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 44, alinea 250. 27 Lihat misalnya: HRC, Concluding Observations on Cameroon, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 36, alinea 203; HRC, Concluding Observations on Togo, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 44, alinea 250. 28 HRC, Concluding Observations on the Russian Federation, UN. Doc. A/59/40 Vol. I (2003) 20, alinea 64(13). 29 30 HRC, Concluding Observations on Portugal, UN. Doc. A/58/40 Vol. I (2003) 56, alinea 83(8). 31 Barbato vs. Uruguay, CCPR/C/17/D/84/1981. 32 Baboeram dkk.. vs. Suriname, CCPR/C/24/D/148/1983. 33 Miango vs. Zaire, CCPR/C/31/D/194/1985. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 15 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court 3. July 2006 Pasal 7 ICCPR Pasal 7 ICCPR menyatakan bahwa “(t)idak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa baik Pasal 1(9) dan Pasal 27 UndangUndang KKR bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR. (a) Pasal 1(9) Undang-Undang KKR Telah dinyatakan bahwa Pasal 1(9) Undang-Undang KKR melanggar Pasal 7 ICCPR dikarenakan pasal UU KKR tersebut bertentangan dengan kewajiban untuk menginvestigasi praktik-praktik penyiksaan dan kewajiban untuk menyeret pihak yang bertanggungjawab. (i) Komentar Umum Di dalam Komentar Umum 2034 mengenai pengimplementasian Pasal 7 ICCPR, HRC berkomentar bahwa “[m]ereka yang melanggar Pasal 7—entah dengan memberikan dukungan, memberikan perintah, memberikan toleransi atau melakukan praktik-praktik yang dilarang—haruslah dimintakan pertanggunjawabannya”.35 Sebagai tambahan HRC mengamati bahwa “[p]emberian amnesti pada umumnya adalah tidak berkesesuaian dengan kewajiban Negara-Negara untuk mengivestigasi praktik-praktik semacam itu, untuk memberikan jaminan tidak terjadinya praktik-praktik semacam ini di dalam ICCPR General Comment (Komentar Umum) 20 (Sesi ke-44, 1992): Pasal 7: Menggantikan Komentar Umum 7 berkenaan dengan Pelarangan atas penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Penghukuman, A/47/40 (1992) 193. 34 ICCPR General Comment 20 (Sesi ke-44, 1992): Pasal 7: Menggantikan Komentar Umum 7 berkenaan dengan Pelarangan atas penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Penghukuman, A/47/40 (1992) 193 pada alinea 13. 35 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 16 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 yurisdiksinya, serta memastikan bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi di masa mendatang”.36 Sebagai konsekuensinya, adalah jelas bahwa di dalam pandangan HRC, pemberian amnesti adalah tidak sesuai dengan Pasal 7 ICCPR. (ii) Catatan Penutup Di dalam Catatan Penutupnya tahun 1993 atas Senegal, HRC mengutuk pemberian amnesti kepada para pelaku kejahatan HAM, khususnya penyiksaan.37 Serupa dengan Catatan Penutupnya tahun 1995 atas Haiti HRC berkomentar bahwa “adalah menjadi keprihatinan kami bahwa…Undang-Undang Amnesti akan dapat menghalanghalangi investigasi atas dugaan-dugaan kejahatan HAM seperti… penyiksaan”.38 Terlihatlah bahwa pemerian amnesti seperti yang tercantum pada Pasal 1(9) Undang- Undang KKR bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR. (iii) Yurisprudensi Kasus Rodríguez vs. Uruguay menggambarkan pandangan HRC bahwa pemberian amnesti tidaklah boleh diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang diatur oleh Pasal 7 ICCPR.39 Di dalam hal ini, Rodríguez telah mengalami penyiksaan oleh pihak aparat Negara. Kemudian Negara memberlakukan sebuah Undang-Undang Amnesti yang memaafkan para pelaku, yang tidak memungkinkan penuntutan atas ICCPR General Comment 20 (Komentar Umum) (Sesi ke-44, 1992): Pasal 7: Menggantikan Komentar Umum 7 berkenaan dengan Pelarangan atas penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Penghukuman, A/47/40 (1992) 193 pada alinea 15. 36 37 HRC, Concluding Observations on Senegal, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 23, alinea 112. 38 HRC, Concluding Observations on Haiti, UN. Doc. A/50/40 Vol. I (1995) 46, alinea 230. 39 Rodríguez vs. Uruguay, CCPR/C/31/D/194/1985. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 17 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 sehingga kejahatan-kejahatan mereka. HRC mendapati bahwa Undang-Undang Amnesti ini adalah “tidak sesuai dengan kewajiban dari Negara pihak di bawah Kovenan”. (b) Pasal 27 Undang-Undang KKR Telah dinyatakan bahwa Pasal 27 Undang-Undang KKR melanggar Pasal 7 ICCPR dikarenakan larangan atas praktik penyiksaan juga mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada para korbannya. Kewajiban ini tidaklah bisa dilaksanakan secara tuntas jika pemberian kompensasi digantungkan pada pemberian amnesti. (i) Komentar Umum Di dalam Komentar Umum 2040 HRC menyampaikan pandangan bahwa “Negara tidaklah diperkenankan untuk menghalangi individu-individu dari hak untuk memperoleh pemulihan efektif, termasuk kompensasi serta rehabilitasi sepenuh-penuhnya.”41 Sebagai konsekuensi, terlihatlah bahwa pemberian syarat atas kompensasi di bawah keharusan untuk memberikan amnesti dapat dipandang sebagai pelanggaran Pasal 7 ICCPR. (ii) Catatan Penutup Telah berulang-kali HRC mengobservasi bahwa terdapatlah sebuah kewajiban untuk memberikan kompensasi para korban penyiksaan. Misalnya saja di dalam Catatan Penutupnya tahun 1995 atas Paraguay, HRC menyatakan bahwa “Negara pihak seharusnya…menyediakan kompensasi patut bagi para korban, khususnya berkenaan ICCPR General Comment 20 (Sesi ke-44, 1992): Article 7: Menggantikan Komentar Umum 7 berkenaan dengan Pelarangan atas penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Penghukuman, A/47/40 (1992) 193. 40 ICCPR General Comment 20 (Sesi ke-44, 1992): Article 7: Menggantikan Komentar Umum 7 berkenaan dengan Pelarangan atas penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Penghukuman, A/47/40 (1992) 193 pada alinea 15. 41 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 18 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 dengan berlanjutnya praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan-perlakuan sewenangwenang oleh pihak kepolisian dan angkatan bersenjata.42 Di dalam Catatan Penutupnya tahun 1999 atas Meksiko, HRC khususnya amat prihatin sehubungan dengan larangan atas penyiksaan serta keharusan untuk memberikan pemulihan, termasuk kompensasi. HRC menyatakan: Adalah merupakan sebuah keprihatinan mendalam…bahwa tidak semua bentuk penyiksaan dicakup secara penuh di dalam Undang-Undang negara Meksiko; dan tidak terdapat badan independen untuk menginvestigasi berbagai laporan/pengaduan atas praktik-praktik penyiksaan serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi atau tidak bermartabat lainnya. Adalah merupakan sebuah keprihatinan pula bahwa praktik-praktik penyiksaan, penghilangan paksa dan pembunuhan ekstra-yudisial yang telah terjadi tidaklah diinvestigasi; bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut tidak kunjung diseret ke pengadilan; dan bahwa para korban atau para keluarganya tidak juga mendapatkan kompensasi. Negara pihak seharusnya mengambil tindakan-tindakan perlu untuk menjalankan secara penuh ketentuan Pasal 6 dan 7 Kovenan, termasuk tindakan pemberian pemulihan atas seluruh penyiksaan di Negara Meksiko.43 (iii) Yurisprudensi HRC telah mengadopsi posisi yang sama di dalam yurisprudensinya sebagaimana yang termuat di dalam Komentar Umum dan Catatan Penutup, bahwasanya para korban penyiksaan harus mendapatkan kompensasi. Sebagai contoh di dalam kasus Muteba vs. Zaire44 HRC mendapati bahwa Negara diwajibkan untuk membayarkan kompensasi kepada Mr. Muteba sebagai bagian dari pemulihan atas penyiksaan yang telah HRC, Concluding Observations (Catatan Penutup) on Paraguay, UN. Doc. A/50/40 Vol. I (1995) 42, alinea 216. 42 Concluding Observations on Mexico, UN. Doc. A/54/40 Vol. I (1999) 61, alinea 318. Lihat juga contohcontoh berikut ini: HRC, Concluding Observations on Niger, UN. Doc. A/48/40 Vol. I (1993) 88, alinea 423; HRC, Concluding Observations on Cameroon, UN. Doc. A/49/40 Vol. I (1994) 36, alinea 203; HRC, Concluding Observations on Argentina, UN. Doc. A/50/40 Vol. I (1995) 35, alinea 161; HRC, Concluding Observations on Bolivia, UN. Doc. A/52/40 Vol. I (1997) 35, alinea 218. 43 44 Muteba vs. Zaire, CCPR/C/22/D/124/1982. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 19 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 dideritanya. Serupa dengan hal ini di dalam kasus Rodríguez vs. Uruguay45 HRC berpandangan bahwa Mr. Rodríguez memiliki hak mendapatkan kompensasi atas penyiksaan yang telah dipaksakan untuk ditanggungnya. 45 Rodríguez vs. Uruguay, CCPR/C/22/D/124/1982. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 20 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court B July 2006 Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (“CAT”)46 ICTJ menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang KKR yang memperbolehkan amnesti dan membebani syarat pemberian reparasi dengan keharusan memberikan amnesti adalah bertentangan dengan CAT. Indonesia menandatangani CAT pada tanggal 23 Oktober 1985. Berkesesuaian dengan Pasal 18 dari Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian (Law of Treaties), maka ketika sebuah Negara telah menandatangani sebuah traktat, maka “Negara tersebut terikat untuk tidak melakukan praktik-praktik yang akan dapat menggugurkan maksud dan tujuan” dari traktat tersebut. Oleh karena itu semenjak tahun 1985 sampai seterusnya, Indonesia dikenakan kewajiban untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik yang akan dapat menggugurkan maksud dan tujuan dari CAT (Konvensi Anti Penyiksaan) tersebut. Indonesia meratifikasi CAT pada tanggal 28 Oktober 1998. ICTJ menyatakan bahwa Undang-Undang KKR melanggar CAT. 1. Pasal 1(9) dan 44 UU KKR melanggar Pasal 4, 7, 12 dan 13 CAT Sebagaimana dinyatakan di atas, Pasal 1(9) Undang-Undang KKR menyebutkan bahwa amnesti “adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [sic]”. 46 G.A. Res. 39/46, Annex, 39 U.N. GAOR Supp. No. 51, U.N. Doc. A/39/51 (1984). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 21 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Pasal 44 Undang-Undang KKR menyatakan bahwa “[p]elanggaran hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad-hoc [sic].” Menurut dengan Pasal 4 CAT, tiap Negara harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya” dan harus “mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya”. Sesuai Pasal 7 CAT, tiap Negara harus “mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan”. Lebih jauh lagi Pasal 12 CAT menegaskan bahwa tiap Negara harus “menjamin agar instansiinstansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya”. Akhirnya Pasal 13 CAT menegaskan bahwa tiap Negara harus “menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihakpihak yang berwenang”. Maka CAT mewajibkan Negara untuk melakukan investigasi, penuntutan dan memberikan pemulihan efektif berkenaan dengan praktik-praktik penyiksaan. ICTJ menyatakan bahwa Pasal 1(9) dan 44 Undang-Undang KKR melanggar kewajiban-kewajiban pokok ini. Di dalam Catatan Penutup tahun 2002 atas Indonesia, Komite Anti Penyiksaan (“Torture Committee”) menyampaikan keprihatinannya atas “kegagalan Negara pihak untuk mengantisipasi secara tepat, tidak berpihak serta melakukan investigasi penuh atas sekian banyak dugaan penyiksaan…demikian pula halnya dengan kegagalan untuk PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 22 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 melakukan penuntutan atas berbagai dugaan pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi”. 47 Di dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Amnesti Peru, Komite Anti Penyiksaan mengutip—dengan ketidaksetujuan—mengenai “Undang-Undang Amnesti yang mengenyampingkan penuntutan atas para tersangka penyiksa, padahal menurut Pasal 4, 5 dan 12 Konvensi, perbuatan tersebut haruslah diinvestigasi dan dituntut”. Menurut Komite Anti Penyiksaan, “Undang-Undang Amnesti seharusnya justru mengecualikan penyiksaan dari cakupan mereka”.48 Serupa dengan hal ini, pada Catatan Penutup tahun 2000 atas Azerbaijan Komite Anti Penyiksaan mengamati bahwa “[d]alam rangka memastikan agar para pelaku penyiksaan tidak dapat menikmati impunitas, Negara pihak harus memastikan bahwa investigasi—dan sejauh dimungkinkan—penuntutan atas mereka yang diduga melakukan kejahatan penyiksaan, serta memastikan bahwa Undang-Undang Amnesti tidak memasukkan penyiksaan dari jangkauannya”.49 Lebih lanjut lagi di dalam kasus Hajrizi Dzemajl dkk. vs. Serbia dan Montenegro50 Komite Anti Penyiksaan mengkonfirmasikan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menginvestigasi, menuntut serta menghukum mereka yang bertanggungjawab atas praktik-praktik penyiksaan. Di dalam kasus M’Barek vs. Tunisia51 47 CAT, Concluding Observations on Indonesia, UN. Doc A/57/44 (2002) 22, alinea 43. 48 CAT, Concluding Observations on Peru, UN. Doc A/55/44 (2000) 13, alinea 59, 61. 49 CAT, Concluding Observations on Azerbaijan, UN. Doc A/55/44(2000) 16, alinea 69. 50 Hajrizi Dzemajl dkk. vs. Serbia and Montenegro UN Doc CAT/C/29/D/161/2000. 51 M’Barek vs. Tunisia (60/1996), U.N. Doc. CAT/C/23/D/60/1996 (2000) alinea 12. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 23 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 dan Blanco Abad vs. Spanyol52 Komite Anti Penyiksaan menyatakan bahwa sebuah Negara melanggar Pasal 13 Konvensi [“CAT”] ketika Negara ini gagal melangsungkan investigasi independen atas dugaan-dugaan praktik penyiksaan di dalam wilayah kewenangannya. Sebagai konsekuensinya adalah jelas dari Catatan Penutup serta yurisprudensi yang ada jika Komite Anti Penyiksaan mengukuhkan bahwa ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1(9) dan 44 Undang-Undang KKR—yang mempersulit investigasi efektif, penuntutan serta penghukuman atas pelanggaranpelanggaran CAT—itu sendiri merupakan pelanggaran dari Konvensi ini. 2. Pasal 27 UU KKR melanggar Pasal 14(1) CAT Sebagaimana telah dinyatakan di muka, Pasal 27 Undang-Undang KKR menyebutkan bahwa “[k]ompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Pasal 14(1) CAT menyatakan bahwa Setiap Negara Pihak (Anggota) harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi. Telah dinyatakan bahwa Pasal 27 Undang-Undang KKR melanggar Pasal 14(1) CAT karena—dengan menempatkan kompensasi di bawah syarat pemberian amnesti— maka pasal ini bertentangan dengan hakikat hak atas kompensasi yang [seharusnya diberikan] tanpa bersyarat. 52 Blanco Abad vs. Spain (59/1996), UN Doc CAT/C/20/D/59/1996 (1988). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 24 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Di dalam berbagai Catatan Penutup Komite Anti Penyiksaan telah menyorot kewajiban absolut bagi Negara untuk menyediakan kompensasi bagi para korban penyiksaan. Misalnya di dalam Catatan Penutup tahun 1995 atas Italia, Komite Anti Penyiksaan mengamati bahwa “Negara pihak seharusnya: Memberikan jaminan lebih baik bagi korban penyiksaan untuk dikompensasikan oleh Negara serta menyediakan sejumlah program rehabilitasi baginya”.53 Serupa dengan hal ini, pada Catatan Penutup atas Peru di tahun 1998, Komite Anti Penyiksaan menegaskan bahwa “[N]egara pihak seharusnya memandang—sesuai dengan Pasal 6, 11, 12, 13 dan 14 Konvensi—agar mengambil tindakan-tindakan demi memastikan bahwa para korban penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta para ahli warisnya, menerima pemulihan, kompensasi dan rehabiitasi di bawah kondisi apa pun”.54 Yurisprudensi Komite Anti Penyiksaan juga prihatin atas kewajiban pemberian kompensasi. Misalnya di dalam kasus Hajrizi Dzemajl dkk. vs. Serbia dan Montenegro Komite Anti Penyiksaan mendesak Serbia dan Montenegro “untuk melancarkan investigasi patut atas praktik-praktik yang telah terjadi pada tanggal 15 April 1995; agar menuntut dan menghukum orang-orang yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan tersebut serta menyediakan pemulihan bagi mereka yang dirugikan, termasuk kompensasi yang patut dan setara”.55 53 CAT, Concluding Observations on Italy, UN. Doc A/50/44 (1995) 21, alinea 157. 54 CAT, Concluding Observations on Peru, UN. Doc A/53/44 (1998) 22 alinea 205. 55 Hajrizi Dzemajl dkk. vs. Serbia dan Montenegro (161/2000), CAT, A/58/44 (21 November 2002). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 25 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court C July 2006 Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa Pada tanggal 25 September 2005 Konvensi Internasional tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa (“Konvensi Penghilangan”) diberlakukan. Kelompok Kerja Penghilangan Paksa atau Tidak dengan Sukarela mengajukan permohonan kepada Majelis Umum pada sesi ke-61-nya agar mengadopsi rancangan Konvensi. Pasal 6 dari Konvensi Penghilangan Paksa ini mewajibkan Negara agar memperlakukan para pelaku penghilangan paksa secara pidana bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan mereka. Pasal 24 dari Konvensi Penghilangan ini juga menyatakan bahwa “[t]iap Negara Pihak harus memastikan di dalam sistem hukumnya bahwa para korban penghilangan paksa berhak atas reparasi serta kompensasi yang tepat, setara dan adil”. Sebagai konsekuensinya, adalah jelas jika Pasal 9(1), 27 dan 44 Undang-Undang KKR melanggar segenap rancangan Konvensi ini. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 26 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court II UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI BERTENTANGAN DENGAN SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL TIDAK TERTULIS A 1. July 2006 Deklarasi PBB dan Resolusi-Resolusinya Deklarasi Penyiksaan56 Pasal 10 Deklarasi Penyiksaan diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa tahun 1975 menyatakan bahwa “[j]ika sebuah investigasi menunjukkan bahwa… sebuah tindak penyiksaan…telah terjadi, maka proses [penuntutan] pidana haruslah digelar”. Sesuai dengan Pasal 11 Deklarasi Penyiksaan “[k]etika dibuktikan bahwa sebuah tindak penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia telah dilakukan oleh atau pun di bawah naungan aparat publik, korban haruslah mendapatkan pemulihan dan kompensasi sesuai dengan hukum nasional”. Sebagai konsekuensinya, sesuai dengan Deklarasi Penyiksaan adalah jelas bahwa amnesti yang disediakan oleh Undang-Undang KKR berkontradiksi dengan aspek-aspek fundamental dari hukum internasional. Lebih jauh lagi, sementara Deklarasi PBB menyediakan sejumlah kelenturan bagi Negara-Negara untuk bertindak sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing, adalah jelas bahwa sejumlah bentuk kompensasi atau pemulihan diwajibkan atas segala tindak penyiksaan. Persyaratan kompensasi dengan memberikan amnesti di dalam Pasal 27 Undang-Undang KKR terlihat berkonflik dengan kewajiban ini. Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Diadopsi Majelis Umum lewat Resolusi 3452 (XXX) 9 Desember 1975). 56 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 27 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court 2. July 2006 Deklarasi Penghilangan57 Deklarasi Perlindungan Semua Orang atas Penghilangan Paksa (“Deklarasi Penghilangan”) diadopsi pada tanggal 18 Desember 1992. Deklarasi Penghilangan mewajibkan Negara-Negara [pihak] untuk melembagakan mekanisme hukum bagi pencegahan serta penghukuman praktik penghilangan paksa. Pasal 14 Deklarasi Penghilangan menyatakan bahwa “[t]iap orang yang diduga telah melakukan tindak penghilangan paksa di Negara tertentu, akandihadapkan pada otoritas sipil berkompeten dari Negara yang bersangkutan untuk tujuan penututan dan persidangan (ketika investigasi resmi telah berhasil mengungkap fakta-fakta terkait)”. Lebih lanjut, Pasal 18 secara spesifik menyatakan bahwa “[o]rang-orang yang telah atau pun diduga melakukan kejahatan-kejahatan yang diacu pada pasal 4, alinea 1, di atas, tidaklah boleh menikmati Undang-Undang Amnesti khusus mana pun, atau upaya-upaya sejenisnya yang dapat berefek pada pengenyampingan mereka dari proses penuntutan pidana atau sanksi”. Sebagai konsekuensinya, menjadi jelas bahwa amnesti bagi [para pelaku] penghilangan paksa adalah dilarang oleh Deklarasi Penghilangan dan bahwasanya tuntutan atas perbuatan ini merupakan kewajiban (mandatory). Sebagai tambahan, Pasal 19 Deklarasi Penghilangan menyatakan bahwa Para korban dari praktik-praktik penghilangan paksa serta keluarganya haruslah memperoleh pemulihan dan memiliki hak bagi kompensasi yang setara, termasuk sarana-sarana untuk mendapatkan rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal sebagai akibat dari prakti penghilangan paksa, keturunannya haruslah pula memperoleh hak atas kompensasi. Pengakuan jelas (eksplisit) terhadap hak atas kompensasi ini sebagai sebuah hak yang absolut berkontradiksi dengan Undang-Undang KKR. Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (Diadopsi Majelis Umum lewat Resolusi 47/133 tanggal 18 Desember 1992). 57 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 28 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court 3. July 2006 Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000)58 Di dalam Resolusi 1325 Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui arti penting penuntutan bagi terwujudnya keadilan dan perdamaian. Dewan Keamanan menekankan kewajiban seluruh Negara untuk mengakhiri impunitas dan menuntut mereka yang bertanggungjawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan berbagai kekerasan lainnya atas kaum perempuan dewasa maupun anak-anak; dan persis di sinilah [kami] menekankan kebutuhan untuk mengenyampingkan kejahatankejahatan ini—sejauh mungkin—dari ketentuan-ketentuan amnesti. Berdasarkan hal ini, sesuai dengan Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, “[p]ara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menerima dan mengemban keputusan-keputusan Dewan Keamanan”, Indonesia seharusnya tidak boleh mengambil langkah-langkah yang melanggar resolusi ini. 58 Diadopsi oleh Dewan Keamanan dalam sidang ke-4213, 31 Oktober 2000. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 29 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court B 1. July 2006 Laporan-Laporan Laporan Sekretaris Jenderal PBB Berkenaan dengan Pembentukan Tribunal Khusus untuk Sierra Leone Di dalam Laporannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB berkenaan dengan Pembentukan Tribunal Khusus untuk Sierra Leone, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa “Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten tetap berpegangan pada posisi bahwa amnesti tidaklah dapat diberikan atas kejahatan-kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional”.59 Sebagai konsekuensinya, terlihatlah bahwa Undang-Undang KKR Indonesia gagal mengemban kewajiban ini di hadapan sebuah pernyataan hukum yang sedemikian jelas dan tidak mendua yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Laporan Sekretaris Jenderal mengenai Supremasi Hukum (Rule of Law) dan Keadilan Transisional (Transitional Justice) bagi Masyarakat Berkonflik maupun Pasca Konflik Pada laporannya yang berpengaruh mengenai persoalan keadilan transisional, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian perdamaian yang dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan pernah menjanjikan amnesti bagi genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan HAM berat”.60 Dewan Keamanan (Security Council), Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra Leone, S/2000/915, 4 October 2000, alinea 22. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/661/77/PDF/N0066177.pdf?OpenElement. 59 Dewan Keamanan (Security Council), Report On The Rule Of Law And Transitional Justice In Conflict And Post-Conflict Societies, The Secretary-General, UN. Doc. S/2004/616, (3 Agustus 2004) alinea 10. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement. 60 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 30 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Dengan merekomendasikan perjanjian-perjanjian perdamaian serta resolusi Dewan Keamanan dan mandatnya, Sekjen PBB menyimpulkan bahwa “[m]enolak dukungan pemberian amnesti bagi genosida (genocide), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), termasuk yang kejahatan yang berkaitan dengan etnis, gender serta kejahatan berbasiskan seksual di level internasional (sexually based international crimes); memastikan bahwa tidak ada amnesti yang diberikan sebelumnya, adalah patokan bagi penuntutan di hadapan pengadilan bentukan PBB maupun yang ditopang oleh PBB”.61 Maka menjadi jelaslah bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai institusi berada pada posisi menentang pemberian amnesti atas kejahatan HAM berat. Lebih jauh lagi, Sekjen PBB menyatakan bahwa “terhadap berlangsungnya kejahatan-kejahatan HAM yang meluas, NegaraNegara [pihak] memiliki kewajiban untuk bertindak tidak hanya terhadap para pelaku, namun juga bertindak atas nama para korban—termasuk melalui berbagai ketentuan reparasi”.62 Maka jelasha terlihat bahwa PBB selain memiliki sikap yang amat jelas dalam menentang amnesti, juga mendukung penuh ketentuan reparasi bagi para korban kejahatan HAM berat. Security Council (Dewan Keamanan), Report On The Rule Of Law And Transitional Justice In Conflict And Post-Conflict Societies, The Secretary-General, UN. Doc. S/2004/616, (3 Agustus 2004) alinea 64. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement. 61 Security Council, Report On The Rule Of Law And Transitional Justice In Conflict And Post-Conflict Societies, The Secretary-General, UN. Doc. S/2004/616, (3 Agustus 2004) alinea 54. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement. 62 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 31 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court 3. July 2006 Laporan Pakar Independen berkenaan dengan Prinsip-Prinsip Impunitas Pada tanggal 18 Februari 2005 seorang pakar independen bernama Diane Orentlicher ditunjuk untuk memperbarui Rangkaian Prinsip bagi Perlindungan dan Promosi HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas (Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity) dan agar menyampaikan hasil/laporannya kepada Komisi HAM PBB (United Nations Commission on Human Rights).63 Di dalam resolusi yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2005, Komisi HAM PBB “mencatat dengan penuh penghargaan, laporan pakar independen serta Rangkaian Prinsip bagi Perlindungan dan Promosi HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas yang telah diperbarui (E/CN.4/2005/102 and Add.1) sebagai panduan untuk mendampingi Negara-Negara dalam mengembangkan upaya-upaya efektif memerangi impunitas”.64 Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) kini telah digantikan oleh Dewan HAM PBB (Human Rights Council), yang berwenang memikul keseluruhan mandat dan tanggungjawab Komisi, serta mengemban peran dan tanggungjawab Komisi HAM PBB berkenaan dengan kerja Kantor Komisioner Tinggi HAM (Office of the High Commissioner). Menyadari bahwa Indonesia kini adalah anggota Dewan HAM PBB, maka jelaslah terdapat keharusan (compulsion) bagi Indonesia untuk menjalankan resolusi-resolusi yang telah ditetapkan oleh Komite HAM PBB sebelumnya. Berkenaan dengan topik amnesti Laporan ini menyatakan bahwa “keputusankeputusan terbaru telah mengukuhkan tidak sesuainya (incompatibility) amnesti—yang Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102, (18 February 2005), tersedia di situs: http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/E.CN.4.2005.102.pdf. 63 64 Commission on Human Rights, 60th meeting, UN Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.17 (April 21, 2005). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 32 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 menghantarkan kepada impunitas—dengan kewajiban Negara-Negara untuk menghukum kejahatan-kejahatan serius di bawah hukum internasional”.65 Berkenaan dengan topik reparasi, laporan ini menyatakan bahwa: Sebagaimana yang berulang-kali telah dikukuhkan di dalam yurisprudensi badanbadan berbasiskan traktat (Konvensi/Kovenan HAM PBB) (human rights treaty bodies), “jika kejahatan tersebut …sungguh-sungguh serius”, para korban haruslah mendapatkan pemulihan yang sepenuhnya sah secara hukum (judicial remedies). Tanpa berprasangka terhadap hak ini, pengalaman akhir-akhir ini telah mengukuhkan peran penting program-program nasional bagi pemulihan pasca tragedi kemanusian berskala besar (mass atrocity). Dalam hal ini, sementara jumlah korban lazimnya amatlah besar, program-program pemerintahan dapat memfasilitasikan distribusi reparasi yang wajar, efektif dan tepat. Maka laporan ini juga secara jelas mengukuhkan keharusan menuntut para pelaku kejahatan HAM serta arti pentingnya menegakkan skema-skema reparasi yang komprehensif. Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102, (18 Februari 2005), alinea 50, tersedia di situs: http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/61chr/E.CN.4.2005.102.pdf. 65 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 33 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court C 1. July 2006 Beberapa Prinsip dan Panduan Rangkaian Prinsip bagi Perlindungan dan Promosi HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas yang Diperbarui (Updated) Di dalam resolution tertanggal 21 April 2005 Komisi HAM PBB merujuk dengan penuh persetujuan kepada Rangkaian Prinsip bagi Perlindungan dan Promosi HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas yang Diperbarui66 (“Prinsip Impunitas”). Resolusi ini mendorong “Berbagai negara, organisasi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, untuk menimbang berbagai rekomendasi serta praktik-praktik terbaik yang terkandung di dalam...Prinsip-prinsip yang telah diperbarui tersebut sebagai hal yang amat sesuai dalam mengembangkan dan menerapkan upaya-upaya efektif memerangi impunitas”.67 Di dalam resolusi yang sama Komisi HAM PBB mengakui “bahwa amnesti tidaklah boleh diberikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan-kejahatan HAM maupun kejahatan perang internasional”.68 Sebagaimana dinyatakan di atas, mengetahui bahwa Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB—penerus sah dari Komisi HAM PBB— Indonesia telah terikat untuk berkomitmen agar bertindak sesuai dengan isi resolusi yang telah ditetapkan oleh Komisi HAM PBB sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 19 mengenai Prinsip-Prinsip Impunitas, Negara-Negara haruslah melaksanakan investigasi yang layak atas kejahatan-kejahatan HAM serta harus memastikan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan serius di bawah hukum Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 Februari 2005) http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement. 66 67 Commission on Human Rights, 60th meeting, UN Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.17 (April 21, 2005) alinea 21. Commission on Human Rights, 60th meeting, UN Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.17 (April 21, 2005) alinea 21, alinea 3. 68 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 34 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 internasional dituntut, diadili dan dihukum secara pantas”.69 Lebih lanjut lagi Pasal 24 dari Prinsip Impunitas menyatakan bahwa “Amnesti serta upaya-upaya lainnya janganlah sampai berefek (mendatangkan pengaruh) atas hak para korban atas reparasi”.70 Prinsip ini secara khusus amat relevan dengan Undang-Undang KKR Indonesia, yakni Pasal 27 yang membebankan persyaratan bagi pemberian reparasi di bawah keharusan memberikan amnesti terlebih dulu. Prinsip Impunitas mengonfirmasikan hakikat absolut dari hak atas reparasi di dalam Pasal 31 yang menegaskan bawah “[k]ejahatan HAM yang bermuara pada hak atas reparasi bagi para korban atau pewarisnya, berimplikasi pada tugas Negara untuk memberikan reparasi dan prospek korban untuk memperoleh pemulihan atas tindakan-tindakan pelakunya”. 71 2. Prinsip Dasar dan Panduan bagi Hak atas Pemulihan Pada tanggal 21 Maret 2006 Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengadopsi Prinsip-Prinsip Umum dan Panduan atas Pemulihan dan Reparasi bagi Para Korban Kejahatan HAM Berat serta Pelanggaran Serius atas Hukum Humaniter72 (“Prinsip-Prinsip Hak atas Pemulihan”). Prinsip-prinsip Hak atas Pemulihan Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 Februari 2005) http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement. 69 Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 Februari 2005) http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement. 70 Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 Februari 2005) http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement. 71 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, G.A. Res. 60/147, U.N. Doc. A/Res/60/147 (16 Desember 2005). 72 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 35 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 mengonfirmasikan bahwa Negara-negara memiliki kewajiban untuk menuntut para pelaku kejahatan HAM serta menyediakan reparasi bagi para korban. Kedua prinsip ini dipandang sebagai aspek fundamental bagi hak korban atas pemulihan. Contohnya Pasal 11 menegaskan bahwa seorang korban memiliki “akses terhadap keadilan yang setara dan efektif” maupun “reparasi yang patut, efektif dan tepat” atas penderitaan yang telah ditanggungnya”. Dengan memperhatikan tugas untuk menuntut mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan HAM…Pasal 4 Prinsip-prinsip Hak atas Pemulihan menyatakan bahwa “[d]i dalam kasus-kasus kejahatan HAM berat dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional…negara memiliki tugas untuk menginvestigasi dan—jika terdapat bukti-bukti cukup—bertugas untuk menuntut orang yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan tersebut serta—jika terbukti bersalah—menghukumnya”. Berkenaan dengan hak-hak korban untuk menerima reparasi, Pasal 3 dari Prinsipprinsip Hak atas Pemulihan menyatakan bahwa kewajiban menerapkan hukum internasional mencakup kewajiban menyediakan reparasi. Pasal 15 membahas kewajiban ini dalam rincian yang lebih tajam dan menyatakan bahwa … Reparasi yang patut, efektif dan tepat dimaksudkan untuk mempromosikan keadilan dengan memberikan pemulihan atas kejahatan berat hukum HAM internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter. Reparasi seyogianya dilakukan secara proporsional, setara dengan besarnya kejahatan dan penderitaan yang didatangkannya. Sehubungan dengan hukum nasional (domestic laws) dan hukum humaniter internasional, sebuah Negara haruslah menyediakan reparasi bagi korban dari tindakan aktif (acts) atau pun pembiaran (omissions) yang dapat dibebankan kepada Negara sejauh merupakan kejahatan berat HAM atau pun pelanggaran serius hukum humaniter internasional. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 36 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 D Pernyataan-Pernyataan Representatif Indonesia di Hadapan Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB 1. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Pada tanggal 23 Juni 2006 Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi yang berisi rekomendasi kepada Majelis Umum PBB bahwa Dewan HAM telah mengadopsi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Dalam keterangan pers Perserikatan Bangsa-Bangsa, representatif Indonesia— Wiwiek Setyawati—telah menyatakan bahwa adalah amat penting bagi Dewan [HAM] untuk menempatkan prioritas pada hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan (nonderogable rights). Pembunuhan sewenang-wenang serta praktik-praktik penghilangan paksa haruslah diakhiri. Tidak ada seorang pun yang boleh mengalami penghilangan paksa, dan bahwasanya kita tidak boleh memberikan toleransi (zero tolerance) bagi praktik semacam ini. Konvensi [Penghilangan Paksa] ini akan menjadi dokumen rujukanstandar penting (an important standard-setting document) untuk memberikan perlindungan dari penghilangan paksa.73 Konvensi ini berisi sejumlah Pasal yang dengan jelas mendukung dalil bahwa para pelaku penghilangan paksa haruslah dituntut (lihat bagian I:C di atas). Berkenaan dengan dukungan yang telah diberikan oleh Indonesia atas Konvensi ini, maka agaknya Indonesia juga telah memiliki komitmen di dalam arena hukum internasional—setidaktidaknya atas kejahatan penghilangan paksa—dengan menuntut para pelaku kejahatan ini. Keterangan Pers Dewan HAM, Dewan Menyimpulkan Diskusi mengenai Laporan Pokja berkenaan dengan Draft Konvensi Anti Penghilangan Paksa [Council Concludes Discussion On Report Of Working Group On Draft Convention Against Enforced Disappearance] (27 Juni 2006). 73 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 37 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court 2. July 2006 Laporan Sekretaris Jenderal mengenai Supremasi Hukum (Rule of Law) dan Keadilan Transisional (Transitional Justice) dalam Masyarakat in Konflik maupun Pasca-Konflik Di dalam komentarnya atas laporan Sekretaris Jenderal PBB yang telah disinggung di muka (bagian II:B:2), Rezlan Ishar Jenie, dutabesar Indonesia untuk PBB menyatakan bahwa: Komunitas internasional dan PBB perlu meningkatkan upaya-upaya mereka untuk membantu negara-negara pihaknya dalam memenuhi tujuan keadilan dan supremasi hukum…Misalnya, PBB dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memajukan kesadaran umum dan pemahaman prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional yang sedemikian esensial bagi perwujudan keadilan dan supremasi hukum…Proposal apa pun untuk memperkuat dukungan PBB bagi keadilan transisional dan supremasi hukum di masyarakat mana pun, haruslah dimaksudkan untuk mempromosikan serta mewujudkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Piagam PBB dan hukum internasional…Proses penting lainnya—sebagaimana tercantum di dalam laporan tersebut—adalah pendayagunaan Komisi Kebenaran dan Keadilan, sebagai instrumen yang telah begitu bermanfaat dalam proses pemulihan sejumlah masyarakat pasca-konflik. Sungguh pun Komisi tersebut bukanlah pengganti (substitusi) proses yudisial, kita tidak boleh menganggap enteng kontribusi-kontribusinya.74 Rezlan Ishar Jenie, Dutabesar Indonesia untuk PBB, Pernyataan di hadapan Dewan Keamanan PBB di dalam item agenda “Justice and the Rule of Law: The United Nations’ Role (6 Oktober 2004). 74 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 38 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court III July 2006 UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NASIONAL LAINNYA Pengadilan tertinggi di Chile, Argentina, Peru dan Kolombia telah mengeluarkan putusan-putusan yang membatalkan ketentuan-ketentuan yang memberikan ruang bagi impunitas. Dasarnya adalah karena ketentuan semacam ini bertentangan dengan kewajiban internasional sebagaimana ditetapkan oleh traktat-traktat internasional sebagaimana yang telah diinterpretasikan pengadilan-pengadilan internasional yang otoritatif maupun badan-badan PBB yang dibentuk berdasarkan Kovenan/Konvensi (treaty bodies) lainnya. Sebagai konsekuensinya, pengadilan tertinggi di kesemua negeri tersebut telah memberikan efek nasional atas hukum internasional (have given domestic effect to international law). Patut dicatat pula bahwa dengan pengecualian Kolombia, semua negeri tersebut membentuk komisi-komisi kebenaran sebagai salah satu mekanisme untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM. Betapapun, pengadilan memperlakukan amnesti secara terpisah dari kewajiban untuk menyingkap dan menemukan kebenaran. Pendekatan ini berkesesuaian dengan pernyataan di muka yang telah disampaikan oleh Rezlan Ishar Jenie, Dutabesar Indonesia untuk PBB, bahwa “[p]roses penting lainnya—sebagaimana tercantum di dalam laporan tersebut—adalah pendayagunaan Komisi Kebenaran dan Keadilan, sebagai instrumen yang telah begitu bermanfaat dalam proses pemulihan sejumlah masyarakat pasca-konflik. Sungguh pun Komisi tersebut bukanlah pengganti (substitusi) proses yudisial, kita tidak boleh menganggap enteng kontribusi- PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 39 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 kontribusinya.”75 Telah dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia seharusnya mengikuti praktik pengadilan-pengadilan nasional lainnya maupun pendekatan yang ditegaskan oleh Dutabesar Indonesia untuk PBB dan seharusnya menegaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah penting namun bukanlah merupakan pengganti dari proses penuntutan (prosecution). A Mahkamah Agung Chile Di dalam putusannya baru-baru ini Mahkamah Agung Chile menetapkan bahwa dikarenakan penghilangan paksa merupakan kejahatan berkelanjutan (an ongoing crime) sampai bukti nyata atas kematian korban telah dikukuhkan, sebuah Dekrit Amnesti tahun 1978—mencakup kejahatan-kejahatan HAM yang dilakukan antara tahun 1973-1978— tidak dapat diterapkan untuk kasus Miguel Angel Sandoval Rodríguez.76 Di dalam kasus ini Mahkamah Agung telah berketetapan dan memutuskan vonis atas sejumlah orang atas kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di tahun 1975. Keputusan ini adalah putusan pertama dari Mahkamah Agung Chile yang menyatakan bahwa Undang-Undang Amnesti Chile tidak lagi berlaku. Sementara di waktu-waktu yang lalu Mahkamah Agung telah dengan jelas menyatakan bahwa amnesti tidaklah akan menghalang-halangi investigasi; kini Mahkamah Agung Chile telah lebih jauh lagi melangkah dengan menegaskan bahwa (UU Amnesti) bukanlah halangan bagi penerapan sanksi pidana. Rezlan Ishar Jenie, Dutabesar Indonesia untuk PBB, Pernyataan di hadapan Dewan Keamanan PBB di dalam item agenda “Justice and the Rule of Law: The United Nations’ Role (6 Oktober 2004). 75 Juan Contreras Sepúlveda y otros (crimen) casacion fondo y forma. Corte Suprema, 517/2004. Resolución 22267. 76 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 40 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Selanjutnya, baru-baru ini pada tanggal 17 Juli 2006 Mahkamah Agung Chile menetapkan sebuah putusan yang melucuti kekebalan Jenderal Augusto Pinochet, sehingga terbukalah jalan bagi penuntutan dirinya atas pembunuhan dua pengawal pribadi Salvador Allende. Putusan Mahkamah Agung ini mengukuhkan putusan pengadilan lebih rendah yang terdahulu, yang juga menyatakan bahwa kekebalan Pinochet selaku bekas Presiden tidak lagi berlaku dan memperkenankan jaksa yang tengah menangani kasusnya untuk melanjutkan pemrosesan dirinya atas tuntutan pembunuhan.77 B Mahkamah Agung Argentina Pada tanggal 14 Juni 2005 Mahkamah Agung Argentina yang memeriksa kasus Simón,78 mendeklarasikan dua Undang-Undang—yang memberikan perlindungan bagi para pelaku kejahatan ‘Perang Kotor’ (kejahatan yang terjadi antara tahun 1976-1983) dari tuntutan hukum—sebagai inkonstitusional (unconstitutional) dan batal demi hukum (void). Mahkamah Agung mengonfirmasikan peran prinsip-prinsip HAM internasional dalam menangani kejahatan-kejahatan HAM berat yang berlangsung di tingkat nasional. Pada pokoknya Mahkamah Agung mengonfirmasikan preseden (precedence) kewajiban [hukum internasional] bagi Argentina di atas statuta-statuta biasa (ordinary statutes), yang bermuara pada pembatalan atas larangan penerapan ketentuan hukum nasional yang sebelumnya telah melindungi para pelaku kejahatan HAM berat dari ancaman penuntutan. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Agung Argentina ini telah membuka 77 Eduardo Gallardo, Chilean Court Pinochet’s Loss of Immunity, Associated Press, 17 Juli 2006. Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad. Supreme Court, causa No. 17.768 (14 Juni 2005) S.1767.XXXVIII. 78 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 41 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 pintu bagi penuntutan atas para pelaku kejahatan HAM berat setelah dua dekade proses yang tersendat-sendat. Pada kenyataannya Mr. Simón—seorang pelaku penyiksa dan pembunuh yang nama buruknya amat tersohor—kini tengah dihadapkan ke persidangan bersama dengan kasus-kasus besar lainnya yang juga tengah diproses menuju meja hijau. C Mahkamah Konstitusi Peru Mahkamah Konstitusi Peru telah menegaskan kewajiban Negara Peru untuk menginvestigasi dan mengenakan sanksi terhadap kejahatan-kejahatan HAM, serta revisi atas larangan penggunaan mekanisme prosedural untuk menginvestigasi dan menjatuhi penghukuman berbagai kejahatan yang serius. Di dalam putusannya tertanggal 18 Maret 2004 atas kasus Villegas Namuche79, Mahkamah menyatakan bahwa: adalah tanggungjawab Negara untuk mengadili mereka yang disangka atas kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), dan, kalau perlu, mengadopsi aturan yang lebih ketat demi mencegah—misalnya saja—dikesampingkannya penuntutan atas berbagai kejahatan HAM serius. Penerapan ketentuan-ketentuan ini memungkinkan sistem hukum untuk bekerja secara efektif dan hal ini dibenarkan berbasiskan kepentingan utama memerangi impunitas. Tujuannya tentu saja untuk mencegah mekanisme hukum tertentu yang lazim dipakai demi motif mempertahankan impunitas. Hal ini haruslah senantiasa dicegah dan dihindarkan, karena hanya akan mendorong para pelaku kejahatan untuk kembali mengulangi perbuatan-perbuatan jahatnya dengan dalih balas dendam sehingga dapat melunturkan nilai-nilai yang begitu fundamental bagi masyarakat demokratis, yakni: kebenaran dan keadilan. 79 Berkas No. 2488-2002-HC/TC. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 42 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 Patut dicatat juga bahwa sejumlah pengadilan di tingkat yang lebih rendah telah pula menyerahterimakan putusan yang mengenyampingkan hambatan-hambatan bagi penuntutan berbasiskan keperluan amnesti.80 D Mahkamah Konstitusi Kolombia Pada tanggal 18 Mei 2006 Mahkamah Konstitusional Kolombia menetapkan putusan yang mengukuhkan sebuah kewajiban, bahwa para pelaku kejahatan HAM haruslah dituntut dan bahwa para korbannya harus pula memperolah reparasi.81 Mahkamah Konstitusi ini mengenyampingkan sejumlah ketentuan Undang-Undang 975/2005 yang membenarkan sejumlah praktik pengurangan vonis bagi para kombatan (combatants) tertentu yang telah didemobilisasi. Mahkamah tidak memberikan syarat pemberian pengurangan vonis pada kontribusi efektif atas reparasi korban. Dalam hal ini Mahkamah merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya untuk memperkuat pertimbangannya. Misalnya saja, ketika melakukan pembahasan mengenai hak atas pemulihan hukum, Mahkamah merujuk pada kasus C-228 tahun 2002 yang menerima penolakan masyarakat internasional terhadap mekanisme [hukum] internal yang memperkenankan pemberian impunitas.82 Mahkamah Konstitusi Kolombia juga merujuk pada kasus C-578 tahun 2002, di situ Mahkamah merujuk pada hukum Sebagai contoh, kasus Quinto Juzgado Penal Especial, 5th Special Criminal Court, di dalam resolusinya tertanggal 2 Juli 2003, mendeklarasikan gagasan pengenyampingan demi alasan amnesti serta alasan nebis in idem (double jeopardy) yang tanpa dasar, karena hal ini bertentangan dengan Konvensi HAM Amerika. 80 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006. 81 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006 alinea 4.9.2. 82 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 43 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 internasional yang mengatur bahwa Negara yang berusaha untuk mengupayakan rekonsiliasi haruslah menyediakan perlindungan yudisial efektif atas para korban.83 Sebagai tambahan, Mahkamah Konsititusi juga mengonfirmasikan bahwa “Mahkamah telah menerima bahwa berbagai instrumen internasional yang menghormati hak tiap orang atas pemulihan hukum yang efektif, dan bahwasanya masyarakat internasional menolak mekanisme internal yang memperkenankan impunitas maupun pengaburan kebenaran atas berbagai perisitiwa yang telah sungguh-sungguh terjadi.”84 Ketika menimbang hak atas reparasi Mahkamah juga mengacu pada kasus C-004 tahun 2003. Di dalam kasus ini disimpulkan bahwa hak-hak korban mencakup hak atas reparasi ekonomi, hak atas kebenaran serta hak untuk memperoleh penegakan keadilan.85 Sebagai konsekuensinya, Mahkamah mengenyampingkan pembatasan kompensasi ekonomi yang telah diperkenalkan sebagai hasil dari Undang-Undang 975/2005. Di dalam mempertimbangkan hak atas keadilan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menginvestigasi tindakan-tindakan yang dapat dihukum secara serius.86 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006 alinea 4.9.6. 83 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006 alinea 4.9.11.2 (diterjemahkan dari bahasa Spanyol). 84 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006 alinea 4.9.8. 85 Kasus No.C-370/2006, (D-6032) berkenaan dengan Undang-Undang mengenai Keadilan dan Perdamaian, 18 Mei 2006 alinea 4.9.8. 86 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 44 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court IV July 2006 KESIMPULAN Sebagai hasil dari uraian di muka, maka ICTJ dengan ini menyampaikan bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang KKR Indonesia yang memperbolehkan amnesti dan mensyaratkan pemberian reparasi di bawah keharusan pemberian amnesti terlebih dulu adalah bertentangan dengan sumber-sumber hukum internasional, baik sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah secara jelas menyatakan komitmennya untuk tunduk pada ICCPR dan CAT, nyatanya UndangUndang KKR melanggar kedua traktat ini. Tambahan pula, Undang-Undang KKR ini juga melanggar Deklarasi Penyiksaan (Torture Declaration) dan Deklarasi Penghilangan Paksa (Disappearances Declaration), bertentangan dengan pernyataan-pernyataan resmi yang telah dibuat di dalam berbagai laporan otoritatif Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengabaikan Prinsip-Prinsip Impunitas dan Pemulihan, serta bertolak-belakang dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat sendiri oleh Indonesia di forum Perserikatan BangsaBangsa. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Konstitusional Indonesia seyogianya memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan bahwa sejumlah pengadilan nasional telah merujuk hukum internasional untuk membatalkan Undang-Undang Amnesti nasional. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 45 International Center for Transitional Justice (ICTJ) Amicus Brief to the Indonesian Constitutional Court July 2006 KETERANGAN TERTULIS SAKSI/AHLI PROFESSOR DOUGLAS CASSEL DI HADAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA, 6 JULI 2006 Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi atas kesempatan memberikan keterangan dalam status saya sebagai ahli, berkenaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (untuk selanjutnya “UU Komisi Kebenaran”). Keterangan tertulis saya kepada Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi Indonesia sebenarnya mengacu pada keterangan/kesaksian lisan saya (oral testimony) berupa butirbutir Power Point, yang dipresentasikan pada Public Hearing tanggal 4 Juli 2006 lalu. Kesaksian tertulis ini merupakan tambahan kepada pihak otoritas hukum (authorities) yang ada dan pada bagian-bagian tertentu melakukan telaah—termasuk sejumlah pertimbangan dan putusan sidang Mahkamah Konstitusi Kolombia tertanggal 18 Mei 2006—yang telah membatalkan beberapa bagian dari Undang-Undang Keadilan dan Kebenaran Kolombia. (Kami akan berusaha keras menyediakan terjemahan bahasa Inggris pada bagian operasional dan argumentasi atas hasil persidangan tersebut selekas mungkin kepada Mahkamah ini). RINGKASAN Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gagal mengemban kewajiban Indonesia sebagai sebuah Negara, serta gagal pula menghargai hak-hak korban, keluarga korban dan masyarakat di bawah hukum HAM (hak asasi manusia) internasional mengenai kebenaran, reparasi, dan keadilan. Secara khusus, UU ini gagal memenuhi kriteria minimal internasional dalam hal: • Menyelidiki dan menyingkap kebenaran tentang berbagai kasus genosida (genocide) serta kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 2000, • Menyediakan reparasi kepada korban dan keluarganya, dan • Memproses secara hukum, serta memberi sanksi yang patut atas para pelaku. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 2 JANGKAUAN KETERANGAN SAYA (SELAKU SAKSI/AHLI) • Kesaksian saya terbatas untuk menyatakan apakah UU Komisi Kebenaran konsisten dengan hukum HAM internasional dan hukum humaniter. Tentang cara bagaimana hukum internasional tersebut digunakan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan hal-hal yang berada di dalam jangkauan ahli hukum Indonesia, seperti para hakim dan pengacara. Akan tetapi, saya mengetahui bahwa di dalam kasus mengenai Pemilu, Mahkamah ini merujuk pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. • Kesaksian saya difokuskan pada hukum internasional tentang kejahatan HAM berat dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional, serta secara partikular, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena saya mengerti bahwa kejahatan-kejahatan ini merupakan subyek Undang-Undang Komisi Kebenaran. • Seperti dinyatakan di dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan merupakan salah satu “kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan internasional”.1 • Seperti telah ditekankan dalam kasus hukum internasional (international case law),2 genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma jus cogens (‘norma atau hukum mengikat’, yang tidak boleh di- Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internastional (Rome Statute of the International Criminal Court), diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002, Pasal 1. 1 Lihat misalnya, Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), Trial Chamber, Prosecutor vs. Furundzija, Case IT-95-17/1, Judgment, 10 Desember 1998, alinea 153 (norma anti-penyiksaan adalah jus cogens “karena pentingnya nilai yang dilindungi”). 2 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 3 derogat/dikesampingkan, ‘overriding norms’), yang berlaku lebih daripada normanorma lainnya.3 Norma-norma ini juga mewakili kewajiban erga omnes (‘berlaku bagi semua’) dari Negara, yakni kewajiban yang tidak hanya ditujukan kepada para korban atau pun warganegaranya tersebut, tetapi bagi semua Negara maupun komunitas internasional.4 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties), 23 Mei 1969, diresmikan tanggal 27 January 1980, UN Treaty Series, Vol. 155, p. 331 (tidak diikuti oleh Indonesia, tetapi banyak diakui sebagai Hukum Kebiasaan Internasional). Pasal 53 dari Konvensi tersebut mendefinisikan jus cogens sebagai “norma umum hukum internasional yang sangat mengikat” (“peremptory norm of general international law”), misalnya, “norma yang diterima dan dikenali oleh komunitas internasional sebagai keseluruhan norma yang tidak boleh di-derogat (dikesampingkan) dan hanya dapat dimodifikasi oleh norma terbaru dari hukum internasional yang memiliki kualitas yang sama.” 3 Komite HAM PBB, Komentar Umum 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004 (selanjutnya disebut sebagai “General Comment 31” saja), alinea 2 (“peraturan mengenai hak-hak dasar dari manusia adalah kewajiban erga omnes”). Semua dokumen hak-hak asasi manusia yang dikutip di kesaksian tertulis ini dapat diakes pada situs UN High Commissioner for Human Rights, www.ohchr.org. 4 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 4 SUMBER-SUMBER UTAMA HUKUM INTERNASIONAL YANG DAPAT DIBERLAKUKAN • Di bawah Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan bekerjasama dengan PBB untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia.5 Jangkauan dan isi dari kewajiban-kewajiban ini telah dielaborasi di dalam praktik selanjutnya oleh NegaraNegara PBB di bawah naungan Piagam tersebut. Di bawah hukum perjanjian internasional (international law treaties), praktik Negara-Negara ini amat relevan untuk menginterpretasikan makna Piagam PBB tersebut.6 Praktik-praktik terbaru di bawah otoritas Piagam PBB—di samping instrumen-instrumen lainnya—mencakup “Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan bagi Hak atas Pemulihan dan Reparasi atas Kejahatan hukum HAM internasional yang berat serta Pelanggaran-Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional“ (The Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law), yang disetujui secara penuh oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 2005.7 • Indonesia bukan hanya anggota dari PBB, tetapi juga anggota dari Dewan HAM PBB yang baru, sehingga memiliki tanggungjawab untuk memenuhi “standar tertinggi” di Piagam PBB (UN Charter), 26 Juni 1945, diberlakukan sejak tanggal 24 Oktober 1945. Pasal 55 (c) menyatakan bahwa PBB “akan memberikan penghormatan universal untuk, dan dalam kerangka, hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa membedakan suku, jenis kelamin, bahasa, atau pun agama.” Sesuai dengan Pasal 56, semua negara “bersumpah untuk berpartisipasi dan melakukan tindakan yang sesuai konteks untuk menunjukkan kerjasama” dengan PBB untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dengan Pasal 55. 5 Vienna Convention on the Law of Treaties, catatan kaki 3 di atas, Pasal 31(3) (“Itu semua akan juga diperhitungkan, bersama dengan konteks…(b) setiap tindakan terbaru untuk menerapkan perjanjian, yang ditetapkan dalam persetujuan oleh pihak-pihak terkait dengan penafsirannya…”). 6 Resolusi Majelis Umum PBB (UN General Assembly Resolution) 60/147, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Annex, diadopsi pada tanggal 16 Desember 2005, UN Doc. A/RES/60/147, 21 Maret 2006 (selanjutnya akan disebut sebagai “Prinsip-Prinsip Umum” saja [“Basic Principles”]). 7 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 5 dalam penerapan hak-hak asasi manusia.8 Pada 2005, badan pendahulu dari Dewan tersebut, yakni Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengadopsi Resolusi tentang Impunitas.9 Resolusi tersebut menyatakan, “bahwa amnesti tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan HAM dan pelangaran terhadap hukum humaniter.”10 Resolusi tersebut juga mencatat “dengan penghargaan” atas Rangkaian Prinsip bagi Perlindungan dan Promosi HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas [Terbaru] (Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity),11 sebagai “panduan mendampingi Negara untuk mengembangkan cara yang efektif memerangi impunitas.”12 • Banyak Pasal yang terdapat di dalam Deklarasi Universal HAM13—seperti yang telah dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi ini dalam kasus Pemilu Indonesia dipandang relevan untuk ditafsirkan dalam konteks Undang-Undang Dasar Indonesia—telah diterima secara luas sebagai Hukum Kebiasaan Internasional, yang mengikat semua Negara. Di antaranya adalah Pasal 8, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (effective remedy) dari pengadilan nasional yang kompeten atas tindak pelanggaran hak-hak fundamental yang dijaminkan baginya oleh Konstitusi atau oleh Undang-Undang.” Anggota dari Dewan Hak Asasi Manusia “akan menjunjung standar tertinggi untuk menjaga dan menyebarkan pemenuhan hak-hak asasi manusia… dan akan dipantau kembali…. Selama masa keanggotaan mereka…” Resolusi Majelis Umum PBB Res. 60/251, 15 Maret 2006, UN Doc. A/RES/60/251, 3 April 2006, alinea 9. 8 9 Komisi HAM PBB (UN Human Rights Commission), Resolution 2005/81, Impunity, 21 April 2005. 10 Resolusi 2005/81, alinea 3. Komisi HAM PBB, Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Addendum, Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 Februari 2005, (selanjutnya disebut “Impunity Principles” (PrinsipPrinsip Impunitas)). 11 12 Komisi HAM PBB, Resolution 2005/81, Impunity, 21 April 2005, alinea 20. 13 Majelis Umum PBB, Res. 217 A (III), 10 Desember 1948. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 6 • Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik14—yang juga menjadi sandaran bagi Mahkamah ini dalam kasus Pemilu—juga telah disetujui oleh Indonesia, dan mulai efektif pada bulan Februari 2006. Kovenan ini tidak hanya mengikat pemerintah, tetapi juga semua cabang kekuasaan Negara, termasuk Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.15 Pasal 2 juga mewajibkan semua Negara pihak untuk: o menghormati dan memastikan terlaksananya hak-hak tersebut bagi semua orang di bawah otoritas Kovenan, o mengimplementasikan hak-hak konvensi melalui hukum dan peraturanperaturan lainnya, dan o menyediakan pemulihan yang efektif bagi siapa saja yang hak-haknya dilanggar di bawah Konvensi. • Kovenan ini ditafsirkan secara otoritatif oleh Komite Hak-hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee), yakni badan yang dibentuk untuk memantau dan mendampingi implementasi Kovenan ini, yang terdiri dari 18 orang pakar. Komite tersebut menerbitkan Komentar Umum penafsiran atas Konvensi. Tujuannya untuk membantu Negara-Negara dalam mengajukan laporan dan tuntutan. Komentar Umum 31 menafsirkan Pasal 2 Konvensi. Judulnya adalah The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (Hakikat Kewajiban Hukum Umum yang Mengikat bagi Negara-Negara Pihak Kovenan).16 • Perjanjian PBB lainnya, di mana Indonesia tercatat sebagai Negara pihak adalah Konvensi tentang Penyiksaan17, Konvensi tentang Diskriminasi Rasial,18 serta Majelis Umum PBB, Res. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, diberlakukan tanggal 23 Maret 1976, UN Treat Series, Vol. 999, p. 171. 14 15 Komentar Umum (General Comment ) 31, alinea 4. 16 Komentar Umum 31, catatan kaki no 4 di atas. Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 17 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 7 Konvensi tentang Hak-Hak Anak,19 yang juga berisi ketetapan untuk menyediakan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM. • Beberapa Hukum Kebiasaan Internasional juga mengikat Indonesia. Yang berkaitan langsung dengan UU Komisi Kebenaran adalah: o Konvensi PBB tentang genosida juga mewajibkan Negara untuk menghukum para pelaku, atau menyerahkannya kepada pengadilan internasional.20 Karena Konvensi tersebut merupakan Hukum Kebiasaan International (International Customary Law) maka Indonesia tetap terikat, walaupun belum secara formal menyetujui perjanjian tersebut. o Prinsip umum dari hukum, yang mewajibkan Negara untuk memberikan reparasi kepada korban pelanggaran HAM dilindungi oleh hukum Treatment or Punishment), UN General Assembly Res. 39/46, 10 Desember 1984, disahkan 26 Juni 1987, UN Treaty Series, Vol. 1465, hlm. 85, diratifikasi oleh Indonesia, 28 Oktober 1998, Pasal 14(1): “Setiap Negara Pihak harus menjamin di dalam sistem hukumnya agar korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh gantirugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi”. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) UN General Assembly Res. 2106 (XX), 21 Desember 1965, diresmikan, 4 Januari 1969, UN Treaty Series, Vol. 660, p. 195, diakui oleh Indonesia, 25 Juni 1999, Pasal 6: “Negara-Negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh pemulihan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu”. 18 Konvensi mengenai Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), UN General Assembly Res. 44/25, 20 November 1989, diresmikan 2 September 1990, UN Treaty Series, vol. 1577, p. 3, diratifikasi oleh Indonesia, 5 September 1990, Pasal 39: “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat; atau konflik bersenjata; pemulihan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan”. 19 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, UN General Assembly Res. 260 A (III), 9 Desember 1948, diresmikan, 12 Januari 1951, UN Treaty Series, Vol. 78, hlm. 277, tidak diikuti Indonesia, Pasal V: “Pihak-pihak yang telah menyetujui perjanjian diharuskan untuk bertindak, sesuai dengan Konstitusi mereka, proses legislasi yang dibutuhkan untuk memberikan dampak nyata dari hasil konvensi, dan secara partikular, untuk menyediakan penalti yang efektif bagi pihak yang bersalah atas pembunuhan massal atau tindakan lainnya yang tercantum di Pasal III” Pasal VI lebih jauh menyatakan, “Orang yang dituduh atas pembunuhan massal atau tindakan lainnya yang tercantum di Pasal III dapat digunakan untuk pengadilan yang kompeten di tempat di mana tindakan tersebut dilakukan, atau pengadilan internasional juga dapat mendapatkan yurisdiksi dengan penghormatan terhadap negara-negara yang telah menyetujui perjanjian”. 20 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 8 internasional. Kewajiban ini diakui sejak tahun 1927 di dalam Chorzow Factory, yang dipimpin oleh Pengadilan Permanen Keadilan Internasional (Permanent Court of International Justice).21 21 The Factory at Chorzow (jurisdiction), [1927], PCIJ 2 (26 Juli 1927) hlm. 29. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 9 PENYANDANG KEWAJIBAN DAN HAK Ketika Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan terjadi: Negara Memiliki Kewajiban: • Melakukan penyelidikan yang efektif dan mendalam, serta mengungkapkan kebenaran kepada korban dan masyarakat mengenai Kejahatan HAM Berat, termasuk Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.22 • Menyediakan pemulihan yang layak dan efektif bagi para korban, termasuk reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasaan dan jaminan atas ketidakberulangan,23 dan • Memproses dan memberikan sanksi hukum secara pantas kepada para pelaku, serta tidak memberikan amnesti kepada pejabat Negara yang terlibat, kecuali jika mereka telah dituntut di hadapan pengadilan (they have been prosecuted before a court of law) .24 Korban dan Keluarganya Memiliki Hak: • Untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi pada mereka, atau orangorang yang mereka kasihi, termasuk “pengungkapan kebenaran secara utuh ke hadapan publik” (“full and public disclosure of the truth”).25 • Untuk mendapatkan pemulihan yang efektif atas kejahatan HAM yang ditimpakan atas diri mereka26, dan 22 Komentar Umum (General Comment) 31, alinea 3; Impunity Principles 1, 2, 4 dan 19. Komentar Umum 31, Alinea 16; Impunity Principles 1; Basic Principles I(2) (c), 11, 15 and 18; Impunity Principles 1. Beberapa peraturan hukum otoritatif—Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) 18 dan Komentar Umum (General Comment) 31 alinea 16—menjadikan jaminan ketidakberulangan sebagai bagian dari kewajiban negara. Peraturan hukum otoritatif lainnya, di antaranya adalah Prinsip Impunitas 34 dan 35, memperlakukan mereka sebagai bentuk reparasi atau pun sebagai kewajiban tersendiri, Negara diwajibkan untuk menjamin prinsip ketidakberulangan peristiwa tersebut. 23 24 Basic Principles II(3) (b), 4, IX.22 (f); General Comment 31, alinea 18; Impunity Principles 1, 19, 22 dan 24. 25 Basic Principles IX(22) (b); Impunity Principles 4. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 10 • Untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk proses hukum dan penghukuman terhadap para pelaku (sungguhpun pada pokoknya ini adalah kewajiban Negara, yang terlepas dari pemenuhan hak bagi para korban).27 Masyarakat Memiliki Hak: • Untuk mengetahui secara utuh tentang kejahatan masa lalu (the full truth of past violations), mengapa kejahatan tersebut terjadi dan oleh siapa, sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan tersebut di masa yang akan datang,28 dan • Atas upaya-upaya efektif yang dibangun agar kejahatan tersebut tidak akan terulang kembali, termasuk dengan cara menghukum para pelaku yang bersangkutan.29 Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights), Pasal 8; Civil and Political Covenant, Pasal 2 (c); Basic Principles VIII.12; Impunity Principles 31 and 32; General Comment 31, alinea 15. 26 Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) IX (22) (f) (hak korban untuk “sanksi hukum dan administratif terhadap orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran”); Impunity Principles 19 (“Walaupun keputusan untuk menghukum terletak dibawah kompetensi negara, korban, dan keluarga mereka serta para pewaris mereka, tetapi proses hukum harus terus berlangsung…Secara partikular sebagai parties civiles, atau sebagai orang yang melakukan penghukuman privat di negara, di mana hukum dan prosedur pidananya mengenali prosedur ini. Negara harus menjamin terlaksananya proses hukum terhadap pihak yang bersalah…”). 27 28 Impunity Principles 2. 29 Impunity Principles 35. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 11 PENYELIDIKAN DAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN KEPADA PUBLIK Ada Dua Kewajiban Negara • Untuk menyampaikan kepada korban dan keluarga mereka tentang kejahatan yang terjadi atas diri mereka serta orang-orang yang mereka kasihi, termasuk sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan HAM berat tersebut terjadi.30 • Untuk menyampaikan kepada masyarakat perihal kebenaran sesungguhnya tentang kejahatan HAM yang telah terjadi, sebab-musababnya dan situasi yang melingkupi terjadinya kejahatan tersebut, sehingga keberulangannya dapat dicegah.31 Sumber dari Kewajiban ini (antara lain): • Kewajiban Negara untuk “memastikan” terlaksananya hak di bawah Pasal 2(1) Kovenan ini,32 • Kewajiban Negara untuk mengukur implementasi hak-hak di bawah Pasal 2(2) Kovenan ini, • Kewajiban Negara untuk menyediakan reparasi dan pemulihan yang efektif kepada korban di bawah Pasal 2(3) Kovenan ini.33 Penyelidikan Haruslah: • Mendalam dan efektif,34 tidak hanya menyelidiki pelaku lapangan/langsung (direct perpetrators), tetapi juga mereka yang berada di level lebih tinggi, yang mungkin 30 Impunity Principles 4; Basic Principles IX(22) (b), X(24). 31 Impunity Principles 2. Komite HAM PBB (UN Human Rights Committee), Komentar Umum (General Comment) 20, 10 Maret 1992, alinea 15:“…Beberapa negara telah memberikan amnesti berkaitan dengan tindakan penyiksaan. Pengampunan tidaklah cocok dengan kewajiban negara untuk menyelidiki tindakan semacam itu; untuk menjamin kebebasan di dalam wilayah yurisdiksi mereka, dan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak lagi terjadi di masa depan. Negara tidaklah boleh mengurangi hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, termasuk kompensasi dan rehabilitasi penuh..” 32 33 Komentar Umum 31, alinea 15. 34 Komentar Umum 31, alinea 15; Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) II(3) (b); Impunity Principles 19. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 12 telah memberikan perintah/komando, atau terkait dengan kejahatan, atau telah mengetahuinya namun gagal untuk mengambil tindakan masuk yang patut untuk mencegah, atau menangkap pelakunya,35 dan • Dilakukan atas dasar inisiatif Negara, dan tidak bergantung pada inisiatif korban, ketika Negara telah menjadi sadar akan informasi mengenai dugaan perbuatan aktif (commission) atas kejahatan HAM berat. • Kewajiban untuk menyelidiki adalah kewajiban yang berkelanjutan, bahkan untuk problem kejahatan HAM yang telah lama berselang. Dengan demikian, Indonesia memiliki tugas di bawah Kovenan untuk menyelidiki kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu, bahkan ketika kejahatan itu terjadi sebelum Indonesia menjadi Negara pihak dari Kovenan ini.36 • Kegagalan untuk menyelenggarakan penyelidikan itu sendiri adalah sebuah pelanggaran HAM tersendiri, dan membuat Negara bertanggungjawab atas pelanggaran lainnya, bahkan kalaupun kejahatan masa lalu itu sendiri belum dibuktikan.37 35 Lihat Prinsip-Prinsip Impunitas (Impunity Principles) 27(b). Di dalam kasus Acuna Inostroza vs. Chile, Communication 717/1996, Pertimbangan (Views) 23 Juli 1999 (dan dalam kasus yang serupa tentang Chile), Komite HAM PBB mendapati bahwa sebuah pengaduan atas kejahatan HAM berat yang terjadi di tahun 1970-an (jauh sebelum Chile meratifikasi Kovenan tersebut dan menerima kompetensi Komite HAM PBB untuk menerimakan pengaduan individu [individual complaints]) tidak dapat ditanggapi (inadmissible). Betapapun, begitu menerima kompetensi Komite, Chile melampirkan sebuah pernyataan kesepahaman tertulis yang menerima kompetensi Komite atas kejahatan-kejahatan yang terjadi pasca tahun 1990. Lihat dalam Pertimbangan, alinea 6(2). Sementara di sisi lain, Indonesia tidak melampirkan pembatasan kurun waktu (temporal) apa pun, ketika Indonesia menerima (acceded) Kovenan ini di tahun 2006. Oleh karena itu Indonesia terikat/harus tunduk pada (subject to) peraturan-peraturan biasa (ordinary rule of international law); bahwa Negara-Negara tetap bertanggungjawab atas kejahatan HAM yang berkelanjutan. Sebagai contoh lihat Inter-American Court of Human Rights, Blake vs. Guatemala, Preliminary Objections, Judgment of July 2, 1996, alinea 39-40. 36 37 Komentar Umum 13, alinea 8(18). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 13 UU Komisi Kebenaran di Indonesia gagal memenuhi standar ini, karena: • Batas waktu 90 hari untuk penyelidikan terlalu singkat untuk menyelidiki kejahatan terhadap masa lalu dan genosida. Di Negara-Negara besar, penyelidikan tersebut bahkan bisa memakan waktu beberapa dekade.38 • Definisi hukum tentang kebenaran, sebagai kebenaran dari sebuah peristiwa semata (‘incident’), tidak mengacu kepada arti kebenaran yang lebih luas, dengan menyingkap sebab dan pola dari kejahatan HAM yang terjadi, termasuk juga situasi dan konteksnya, serta pelajaran yang bisa diambil sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida tersebut tidak terulang lagi.39 • Terlampau kecilnya insentif (dorongan) bagi para pelaku untuk mengaku menyatakan kebenaran dan untuk mendapatkan amnesti, terutama karena terlampau minimnya ancaman hukuman, kalaupun mereka tidak melakukan hal tersebut (tidak mau mengaku). • Tidak ada persyaratan yang jelas dan tegas bahwa pelaku yang hendak meminta amnesti akan memberikan kesaksian mengenai kebenaran sesungguhnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui.40 • Korban akan merasakan tekanan untuk “memaafkan”, bahkan kalaupun kebenaran tidak diungkapkan dengan sepenuh-penuhnya/utuh (not fully told), sehingga pelaku dapat memperoleh amnesti dan korban memperoleh reparasi. Di bawah UndangUndang KKR yang ada, jika pelaku tidak mendapatkan pengampunan, maka korban pun tidak akan mendapatkan reparasi.41 38 Pasal 24 UU KKR Indonesia. 39 Pasal 1(1) UU KKR Indonesia. 40 Pasal Pasal 23, 28.2 UU KKR Indonesia. 41 Lihat Pasal Pasal 27, 28 dan 29 UU KKR Indonesia. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 14 REPARASI BAGI KORBAN DAN KELUARGA MEREKA Para korban memiliki hak untuk mendapatkan ‘pemulihan yang efektif’ (effective remedy) (lihat di muka). Orang yang ‘mengklaim’ bahwa dirinya adalah korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, agar sebuah proses yudisial atau pun proses administratif yang adil dapat menentukan apakah mereka—dalam kenyataannya—adalah sungguh-sungguh korban, sehingga memang layak mendapatkan reparasi.42 Sumber hukum utama yang menyatakan tentang hak korban untuk mendapatkan pemulihan adalah (antara lain): • Pasal 8 Deklarasi Universal, • Pasal 2(3) Kovenan, dan • Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) PBB. Metode pemulihan yang efektif mencakup akses yang setara dan efektif terhadap keadilan, akses kepada informasi yang relevan berkaitan dengan kejahatan yang terjadi dan mekanisme reparasi.43 Reparasi, dengan demikian, mencangkup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (satisfaction) dan jaminan bahwa kejahatan tidak akan terulang lagi.44 42 Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) II(3) (c). 43 Prinsip-Prinsip Umum VII(11). 44 Prinsip-Prinsip Umum IX(18); lihat catatan kaki 23 di atas. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 15 UU Komisi Kebenaran di Indonesia gagal memenuhi standar ini, karena: • Kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan hanya jika permohonan amnesti telah diberikan.45 • Dengan demikian di dalam banyak kasus, kompensasi dan rehabilitasi ini tidak akan mungkin dapat diberikan. Misalnya ketika pelaku tidak dapat diidentifikasi atau gagal dalam pengajuan amnesti, atau tidak dimaafkan oleh korban, atau dianggap tidak layak oleh Presiden atau oleh DPR.46 • Di dalam versi terjemahan bahasa Inggris tak resmi atas UU KKR, setidaknya terdapat ketidakjelasan atas UU Komisi Kebenaran ini; contoh: kapan sebenarnya restitusi—metode yang dianggap layak sebagai bentuk reparasi di bawah hukum internasional—sungguh-sungguh dapat diberikan.47 • Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dapat ditunda sampai tiga tahun, walaupun tidak ada pembenaran yang signifikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.48 • Tidak ada ketentuan yang ditetapkan untuk mengukur kepuasan (satisfaction), seperti pengakuan publik atas fakta-fakta yang dipaparkan, penerimaan atas pertanggungjawaban Negara, permintaan maaf dari Negara dan pembangunan monumen-monumen peringatan akan korban.49 • Tidak ada ketentuan yang menjamin bahwa kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi, seperti kriteria yang dirumuskan untuk melindungi para pembela hak-hak asasi manusia.50 45 Pasal 27UU KKR Indonesia. 46 Pasal 25-28 UU KKR Indonesia. 47 Pasal 27 UU KKR Indonesia. 48 Pasal 21(1) UU KKR Indonesia. 49 Lihat Pasal 1(6), 1(7) and 1(8) UU KKR Indonesia. Lihat Pasal 1(6), 1(7) dan 1(8) UU KKR Indonesia; bandingkan dengan Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) IX(23). 50 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 16 PROSES HUKUM DAN PENGHUKUMAN Hukum internasional mengijinkan dan bahkan mendorong adanya amnesti bagi setiap kejahatan, tetapi bukan atas Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Sumber hukum utama yang dapat digunakan untuk melarang: • Kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang dilindungi oleh Konvensi Pasal 2(1) sebagaimana yang ditafsirkan secara resmi oleh Komite HAM PBB dalam Komentar Umum (General Comment) 31, yang melarang amnesti bagi pejabat publik (public official) atau pun pejabat Negara yang melakukan kejahatan HAM berat.51 • Praktik PBB, sebagaimana yang dikonfirmasikan di dalam laporan Sekretaris Jenderal mengenai Pengadilan Khusus di Sierra Leone tahun 2000,52 dan dikukuhkan kembali oleh laporan Sekretaris Jenderal pada tahun 2004 tentang praktik-praktik terbaik keadilan transisional (transitional justice),53 tidak menerima pemberian amnesti atas pembunuhan massal atau pun kejahatan atas 51 Komentar Umum (General Comment) 31, alinea 18. Laporan Sekjen PBB sehubungan dengan Pembentukan Pengadilan Khusus bagi Sierra Leone, S/2000/915, 4 Oktober 2000, alinea 22: “Sementara [kami] mengakui bahwa amnesti adalah sebuah konsep hukum yang dapat diterima serta merupakan pertanda perdamaian dan rekonsiliasi di penghujung perang saudara maupun konflik bersenjata dalam negeri, PBB secara konsisten telah mengambil sikap bahwa amnesti tidak boleh diberikan atas kejahatan-kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran serius atas hukum humaniter” (“While recognizing that amnesty is an accepted legal concept and a gesture of peace and reconciliation at the end of a civil war or an internal armed conflict, the United Nations has consistently maintained that amnesty cannot be granted in respect of international crimes, such as genocide, crimes against humanity or other serious violations of international humanitarian law”). Lihat juga alinea 23-24. 52 Laporan Sekjen PBB tentang Supremasi Hukum dan Keadilan Transisional di dalam Masyarakat Berkonflik dan Pasca Konflik (Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies), UN Doc. S/2004/616, 23 Agustus 2004, alinea 10: “Perjanjian-perjanjian perdamaian yang difasilitasi PBB tidak akan pernah menjanjikan amnesti bagi genosida, kejahatan-kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan HAM berat” (“United Nations-endorsed peace agreements can never promise amnesties for genocide, war crimes, crimes against humanity or gross violations of human rights”). 53 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 17 kemanusiaan, di antara berbagai kejahatan berat atas hak-hak asasi manusia lainnya. • Kewajiban Negara untuk menghukum atau mengekstradisi di bawah otoritas Konvensi Penyiksaan (Torture Convention) adalah tidaklah konsisten dengan pemberian amnesti bagi para pelaku penyiksaan tersebut.54 • Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak untuk Mendapatkan Pemulihan dan Reparasi (The Basic Principles dan Guidelines on the Right to a Remedy and Reparations) mewajibkan Negara untuk memproses secara hukum dan menghukum orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran berat hak-hak asasi manusia.55 • Resolusi Komisi HAM PBB tentang Impunitas tahun 2005 menyatakan bahwa “amnesti tidaklah boleh diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.”56 • Prinsip-prinsip terbaru yang telah dirumuskan untuk memerangi impunitas melarang amnesti bagi para pelaku kejahatan HAM berat, setidaknya sampai mereka telah dihukum di pengadilan.57 Prinsip tersebut kemudian menekankan bahwa amnesti tidak boleh mempengaruhi hak korban untuk mendapatkan reparasi, atau hak untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi.58 54 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture), catatan kaki 17 di atas, Pasal 7(1). 55 Prinsip-Prinsip Umum (Basic Principles) III(4). 56 Komisi HAM PBB (UN Human Rights Commission), Resolusi 2005/81, Impunity, 21 April 2005, alinea 3. 57 Prinsip-Prinsip Impunitas (Impunity Principles) 24(a). 58 Prinsip-Prinsip Impunitas (Impunity Principles) 24(b). PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 18 • Watak jus cogens dari norma-norma yang melawan semua bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga tidaklah konsisten dengan pemberian amnesti bagi kejahatan-kejahatan ini.59 UU Komisi Kebenaran di Indonesia gagal untuk memenuhi standar ini, karena UndangUndang tersebut memperbolehkan amnesti bagi orang yang melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.60 Lihat Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), dalam Pengadilan Tertutup (Trial Chamber) kasus Penuntut Umum vs. Furundzija, Kasus IT-9517/1, Putusan, 10 Desember 1998, alinea 155: “Fakta bahwa penyiksaan itu dilarang oleh sebuah norma hukum international yang harus dipatuhi ternyata memiliki beberapa dampak… Sesungguhnya tak terbantahkan, bahwa pada satu sisi, nilai-nilai jus cogens mengenai larangan penyiksaan, perjanjian atau aturan-aturan kebiasaan yang mengatur penyiksaan menjadi batal dan tidak berlaku semenjak perbuatan tersebut dilakukan (null and void ab initio), [catatan kaki diabaikan], dan kemudian sebuah Negara, dengan ceroboh, menyatakan telah mengambil tindakan-tindakan yang mengesahkan atau memberi jalan bagi tindakan penyiksaan atau membebaskan para pelakunya melalui hukum amnesti [catatan kaki tidak disertakan]. Bilamana situasi demikian terjadi, tindakan negara tersebut dianggap telah melanggar Prinsip-prinsip Umum dan Kesepakatan lain yang terkait, ..tindakan negara tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan resmi internasional. Penuntutan bisa dilakukan oleh kelompok korban yang memiliki kapasitas hukum (locus standi) badan yudisial yang kompeten baik di tingkat nasional maupun internasional dengan permohonan untuk menahan berlakunya produk hukum nasional tersebut yang bertentangan dengan hukum internasional; atau korban tersebut dapat mengajukan tuntuntan perdata ke pengadilan di negeri asing atas kerugian-kerugian yang dideritanya, yang kemudian, di antara hal-hal lainnya (inter alia), akan diminta untuk tidak mengindahkan keabsahan dari hukum nasional tersebut. 59 Lihat juga Pengadilan Khusus (Special Court) Sierra Leone, Appeals Chamber, Prosecutor vs. Kallon, Kasus No. SCSL-2004-15-AR72(E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lome Accord Amnesty, 13 Maret 2004. Pengadilan ini menetapkan bahwa sebuah amnesti nasional bagi kejahatan-kejahatan pidana internasional yang serius (serious international crimes) tidak dapat mengikat sebuah pengadilan internasional, alinea 72, 88; bahwa ketika kewajiban traktat (sebagaimana terdapat di dalam Konvensi Anti Penyiksaan) mewajibkan Negara untuk menuntut atau mengekstradisi seorang tersangka, maka pemberian amnesti atas kejahatan itu sendiri akan merupakan sebuah “pelanggaran atas kewajiban sebuah Negara terhadap komunitas internasioal secara keseluruhan”, alinea 73; dan [adalah] sebuah norma, bahwa negara yang tidak boleh memberikan amnesti atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius di level pengadilan nasionalnya “kini tengah berkembang di bawah hukum internasional”, alinea 82. Patut dicatat bahwa Pengadilan Khusus Sierra Leone ini mencapai kesimpulan di atas bahkan sebelum Komite HAM PBB mengadopsi Komentar Umum (General Comment) 31 belakangan di tahun 2004; Komisi HAM PBB mengadopsi Resolusi mengenai impunitasnya di tahun 2005. Komisi HAM PBB mencatat dengan penuh penghargaan Rangkaian Prinsip mengenai Impunitas [Terbaru] (updated); dan di tahun 2005 Majelis Umum mengadopsi Prinsip-prinsip Umum atas Reparasi (Basic Principles on Reparations). 60 UU KKR Indonesia, Pasal 24-29. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 19 SEBUAH ALTERNATIF TERHADAP AMNESTI: KURANGI PENGHUKUMAN, MENYATUKAN DENGAN PROSES PENCAPAIAN KEBENARAN, REPARASI DAN PENGHUKUMAN YANG PROPORSIONAL Sebagai alternatif dari amnesti, Negara-Negara juga dapat mengurangi penghukuman sebagai imbalan dari pengakuan para pelaku. Alternatif semacam ini telah diadopsi oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia dan Rwanda. Pengadilan tersebut memberikan hukuman yang lebih ringan bagi para pelaku yang mengaku bersalah, mengaku sepenuhnya atas kejahatan merea dan menunjukkan penyesalan.61 Alternatif untuk mengurangi penghukuman sebagai imbalan dari pengungkapan kebenaran (truth telling) juga dipertimbangkan di dalam prinsip-prinsip terbaru PBB dalam memerangi impunitas.62 Walaupun begitu, penghukuman ini tidaklah dapat dikurangi terlalu banyak. Hukuman haruslah tetap bermakna dan proporsional dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Lebih dari itu, upaya untuk menyingkap kebenaran tetaplah harus dilakukan, waktu yang mencukupi untuk melakukan penyelidikan secara mendalam, serta reparasi yang adekuat (mencukupi) bagi korban. Ini adalah pelajaran yang dapat diambil dari keputusan di Mahkamah Konstitusi Kolombia baru-baru ini, pada 18 Mei 2006, yang mengenyampingkan beberapa bagian penting dari Undang-Undang Keadilan dan Perdamaian Kolombia. Undang-Undang tersebut memperbolehkan pengurangan hukuman bagi kelompok bersenjata ilegal, yang mengakui secara spesifik bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan serius. Enam dari sembilan Hakim Konstitusi memandang bahwa sejumlah ketentuan Undang-Undang tersebut tidak sah, sedangkan tiga Hakim lainnya memandang bahwa keseluruhan Undang-Undang itu Misalnya, Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), Prosecutor vs. Plavsic, Case IT-00-39&40/1, Trial Chamber, Ketetapan Vonis (Sentencing Judgment), 27 Februari 2003, alinea 66-81 (dapat diakses pada situs www.un.org/icty). 61 62 Prinsip-Prinsip Impunitas (Impunity Principles) 28. PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 20 tidak Konstitusi. Tidak ada satu pun Hakim Konstitusi Kolombia yang menyatakan dukungan atas Undang-Undang tersebut. Sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia tersebut—sejauh pengetahuan saya—tidak tersedia di dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya tengah berkonsultasi dengan International Center for Transitional Justice (Pusat Internasional untuk Keadilan Transisional) dan Paul van Zyl, dalam upaya untuk menyediakan terjemahan bahasa Inggris bagi Mahkamah Terhormat ini, setidaknya untuk bagian operasional dan pertimbangan Mahkamah Kolombia tersebut selekas mungkin. Sementara itu, di bawah ini adalah beberapa aspek kunci dari Keputusan Mahkamah Kolombia: • Hukuman Penjara: Undang-Undang Kolombia memperkenankan para anggota kelompok bersenjata ilegal untuk mengaku atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan, sebagai imbalannya adalah pengurangan penghukuman sampai lima atau delapan tahun penjara. Lebih dari 1½ tahun yang dihabiskan di kamp demobilisasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari masa hukuman penjara. Dengan kata lain, periode minimal dari hukuman penjara atas [pelaku] pembantaian massal (massacres) dan berbagai kejahatan keji terhadap warga sipil lainnya dapat berlangsung 3½ tahun (minimal lima tahun, setelah dikurangi 1½ tahun di kamp demobilisasi). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa waktu di kamp demobilisasi tidak dapat dihitung sebagai bagian dari penghukuman penjara, sehingga hukuman minimal adalah tetap lima tahun. • Kebenaran: Mahkamah kemudian menyatakan bahwa pengurangan dari hukuman normal—yakni 5-8 tahun penjara untuk kejahatan-kejahatan serius—haruslah amat digantungkan pada semua kejahatan yang telah diungkapkan. Mahkamah menetapkan, jika di kemudian hari didapati bahwa para pelaku tidak mengakui semua PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 21 kejahatannya, maka hukuman penjara tambahan dapatlah diberikan, berdasarkan sanksi yang lazim diberikan atas kejahatan yang tidak diakui. • Penyelidikan: Undang-Undang hanya menyediakan waktu 60 hari bagi penuntut umum untuk menyelidiki apakah pengakuan para pelaku itu benar atau tidak. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan ini tidak valid, karena waktunya terlalu singkat untuk mengkonfirmasikan kebenaran. • Reparasi: Undang-Undang mewajibkan para pelaku untuk membayar reparasi atas segala harta benda yang telah diambilnya secara ilegal sebagai hasil dari kejahatannya. Mahkamah mewajibkan para pelaku untuk membayar reparasi dari semua harta miliknya, tidak hanya terbatas pada harta yang telah diambilnya secara ilegal. Dengan kata lain, Mahkamah mewajibkan kelompok-kelompok ilegal agar bertanggungjawab secara kolektif dengan membayar reparasi; dan tidak hanya bagi para pelaku individual yang telah mengaku. Hanya ketika pembayaran reparasi yang dilakukan para pelaku tidak mencukupi, [barulah] Negara akan membayarkan reparasi tersebut. • Partisipasi Korban: Pengadilan menyatakan bahwa di dalam proses pengadilan pidana terhadap para pelaku, korban diperkenankan untuk berpartisipasi aktif. Bahkan sebelum keputusan-keputusan ini ditetapkan, Undang-Undang Kolombia telah memberikan hak-hak yang lebih bagi korban, dan telah lebih mendekati [standar] kewajiban Negara—di bawah hukum internasional—untuk menghukum pelaku dan menyediakan reparasi, dibandingkan dengan Undang-Undang Komisi Kebenaran Indonesia. Akan tetapi, seperti yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Kolombia, Undang- PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 22 Undang Kolombia sendiri sesungguhnya tidak memenuhi kriteria standar Konstitusi Kolombia, yang mengacu kepada standar internasional. Akhirnya haruslah dicatat bahwa sementara Undang-Undang Kolombia memang berkenaan dengan kelompok-kelompok bersenjata ilegal, namun Undang-Undang Komisi Kebenaran Indonesia mencakup langsung juga dengan pejabat (officials) serta para agen Negara (agents of the State). Adalah kewajiban Negara untuk menyelidiki dan menghukum pejabat dan agennya sendiri, serta membayarkan reparasi bagi korban-korban mereka. Reparasi dan penghukuman tersebut berada di level pertanggungjawaban yang lebih tinggi daripada proses hukum atas kelompok bersenjata yang ilegal. Diajukan dengan penuh hormat, Douglass Cassel Lilly Endowment Professor of Law Direktur, Center for Civil and Human Rights Notre Dame Law School Notre Dame, Indiana USA [email protected] 6 Juli 2006 PEC – Research Dept. – Translation Unit: Aug. 2006 23 Keterangan Saksi/Ahli Naomi Roht-Arriaza, Professor Hukum, Universitas California, Hastings College of Law, Di hadapan Mahkamah Konstitusi Saya ingin berterimakasih kepada Mahkamah karena telah menenerima keterangan saya, baik keterangan lisan maupun tulisan, dalam kapasitas sebagai ahli berkenaan dengan persoalan mengenai keabsahan Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Undang-Undang KKR). Kesaksian tertulis ini pada pokoknya mengikuti atau menegaskan presentasi lisan saya sebelumnya. Saya mengerti bahwa hukum Indonesia memperbolehkan Mahkamah ini untuk memberikan ruang dan penghargaan yang cukup terhadap hukum internasional, termasuk di dalamnya adalah perjanjianperjanjian yang telah diratifikasi, perjanjian-perjanjian yang belum diratifikasi, serta prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM) internasional maupun deklarasi-deklarasi lainnya. Untuk itulah saya hendak memberikan kesaksian (testimony) tentang kesesuaian (compatibility) KKR dengan hukum internasional berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pemulihan (remedy) serta reparasi (reparation). Secara lebih khusus saya hendak menyorot Pasal 27 Undang-Undang KKR yang menempatkan hak korban atas reparasi tergantung pada pemberian amnesti bagi pelaku, yang melanggar standar internasional, termasuk perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 2 Indonesia. Sebagai tambahan, dengan tidak memberikan hak kepada korban untuk melanjutkan tuntutan ke Pengadilan HAM ketika kasusnya sudah ditangani oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka pasal 44 telah melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi (redress). Hal ini sangat bertentangan dengan praktik Komisi Kebenaran maupun program-program reparasi di level internasional—yang memisahkan kewajiban Negara untuk menyediakan reparasi dengan persoalan amnesti—dan bahwa dalam kasus manapun Negara tidak boleh memberikan amnesti bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Maka dalam pemahaman ini pasal 1(9) Undang-Undang KKR juga bermasalah, karena pasal ini memperbolehkan pemberian amnesti bagi kejahatan-kejahatan yang [sesungguhnya] tidak boleh mendapatkan amnesti di bawah hukum internasional. Komentar saya akan berfokus pada tujuan Komisi Kebenaran, serta kewajiban yang saling berhubungan antara hak atas kebenaran, keadilan dan reparasi. Kemudian saya akan memaparkan definisi “korban” di dalam hukum internasional, serta menjelaskan mengapa definisi tersebut tidak dapat berjalan searah (cannot be contingent) dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional, atau tidak dapat begitu saja diidentikkan dengan amnesti terhadap para pelaku; sehingga haruslah menjadi pertimbangan yang berdiri sendiri (independent determination). Pada bagian akhir, saya akan kembali pada praktik Komisi-Komisi Kebenaran yang telah ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan reparasi dan amnesti. PEC Translation Unit – 2006 3 1. Tujuan Komisi Kebenaran Banyak Negara di dunia telah membentuk Komisi Kebenaran setelah era kediktatoran, periode represi masif, atau pun pasca konflik. Pertama-tama, tujuan Komisi ini sendiri adalah untuk menciptakan catatan otoritatif yang sah atas fakta-fakta yang ada (an authoritative record of the facts). Tanpa pengetahuan bersama mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu, serta tanpa pengakuan resmi atasnya, suatu tatanan demokrasi yang kukuh tidaklah akan dapat sungguh-sungguh dibentuk. Komisi Kebenaran juga penting untuk memampukan para korban menuturkan kisah mereka agar didengarkan orang banyak. Dalam banyak kesempatan pelanggaran tidak pernah diakui, sehingga korban harus terus menanggung stigma dan pengucilan. Kondisi seperti ini haruslah diubah, agar korban bisa dikembalikan ke dalam masyarakat. Komisi Kebenaran juga menyajikan laporan serta rekomendasi untuk mencegah agar pengulangan kejahatan HAM di masa lalu tersebut tidak terjadi lagi. Beberapa Komisi Kebenaran memang memiliki tujuan untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional. Ide dasarnya adalah, bahwa pengetahuan serta pengakuan tentang peristiwa yang telah terjadi, identifikasi pelaku dan korbannya merupakan faktor yang sangat penting untuk membuka peluang bagi rekonsiliasi. PEC Translation Unit – 2006 4 2. Independen tetapi memiliki kewajiban yang saling terkait Hukum internasional dan penerapannya mengenal tiga bentuk kewajiban Negara yang terpisah, independen namun saling terkait, serta berkaitan langsung dengan hak-hak korban, yakni: hak atas kebenaran, keadilan dan reparasi. Pemenuhan salah satu dari ketiga hak tersebut tidaklah berarti bahwa hak-hak lainnya bisa diabaikan, atau dapat diikat dan kemudian digantungkan pada pemenuhan hak lainnya. Kewajibankewajiban yang berinterrelasi ini muncul dari praktik hukum internasional yang sudah berlangsung lama, maupun dari kewajiban perjanjian-perjanjian internasional spesifik lainnya. Kewajiban Negara untuk memulihkan kerugian/penderitaan akibat pelanggaran HAM yang terjadi telah menjadi salah satu prinsip terpenting di dalam hukum internasional.1 Hak korban untuk mendapatkan pemulihan juga telah dijamin di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian HAM internasional lainnya.2 Hak atas pemulihan (the right to remedy) adalah sebuah konsep yang luas dan tidak hanya mencakup kompensasi finansial saja. Konsep tersebut mencangkup pula hak untuk memperoleh kebenaran dan keadilan serta hak atas reparasi, Pengadilan Internasional untuk Keadilan Permanen (International Court of Permanent Justice), Chorzow Factory, 1928, Series A No. 17, Putusan (judgment) Nº 13. 1 Deklarasi Universal HAM, Pasal 8; Pasal 2(3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights); Pasal 14 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture); Pasal 13 Konvensi Eropa tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar (European Convention on Fundamental Rights and Freedoms); Pasal 25 Konvensi Amerika tentang HAM; Pasal 7 Piagam Afrika tentang HAM dan hak Masyarakat; Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. 2 PEC Translation Unit – 2006 5 yang keseluruhannya berasal dari yurisprudensi badan-badan internasional berkenaan dengan kewajiban-kewajiban perjanjian tersebut (treaty obligations). Dengan demikian, pada kasus Bautista de Arellana vs. Colombia, Komite HAM (Human Rights Committee), dengan menafsirkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (yang telah diratifikasi oleh Indonesia) mendapati bahwa walaupun para pelaku—yang mengemban jabatan-jabatan publik telah diberikan sanksi administratif, serta kompensasi telah diberikan kepada korban—namun kesemuanya itu belumlah cukup, karena Konvensi mewajibkan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan HAM berat. Komite ini menyatakan: 8.2 Dalam ketetapan yang dibuatnya pada 14 Juli 1995, Negara Pihak (the state party) menyatakan bahwa Resolusi 13 pada tanggal 5 Juli 1995 memberikan sanksi displiner terhadap Messrs. Velandia Hurtado dan Ortega Araque; serta Pengadilan Administratif dari Cundinamarca pada 22 Juni 1995 telah mengabulkan klaim kompensasi kepada keluarga Nydia Bautista. Negara pihak menegaskan ulang niatnya untuk menjamin pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar sepenuhnya. Berkenaan dengan hal ini—dalam pandangan Negara pihak—keputusan di atas telah memberikan pemulihan yang efektif bagi keluarga Nydia Bautista. Komite tidak sepaham dengan pandangan semacam ini, karena pengenaan sanksi administratif dan displiner semata tidaklah dapat dianggap cukup serta tidaklah sesuai dengan hak korban atas pemulihan yang efektif, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2, paragraf 3 Konvensi, terutama di dalam peristiwa pelanggaran HAM serius, khususnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap hak atas kehidupan…8.6 Betapapun Komite memandang bahwa Negara pihak memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan berbagai bentuk kejahatan HAM, dan secara spesifik penghilangan paksa serta pelanggaran atas hak hidup, dan PEC Translation Unit – 2006 6 kemudian menuntutnya secara pidana, serta mengadili dan menghukum para pelaku yang bertanggungjawab atas kejahatan semacam itu. Tugas ini berlaku a fortiori di dalam berbagai kasus, ketika para pelaku telah berhasil diidentifikasikan. Komunikasi No.563/1993, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/563/1993 (1995). Beberapa instrumen HAM lainnya memiliki ketentuan yang serupa tentang hak korban atas pemulihan. Komisi HAM Inter-Amerika (InterAmerican Commission on Human Rights) telah lama mengartikan istilah “hak untuk mendapatkan pemulihan” di dalam Konvensi [Negara-Negara] Amerika [Selatan] yang mencakup kewajiban Negara untuk melakukan investigasi dan penuntutan; berulang kali menegaskan investigasi atas fakta-fakta yang ada, menghukum para pelaku yang bertanggungjawab atas tindak penghilangan paksa atau penyiksaan. Komisi HAM InterAmerika juga menemukan kasus serupa atas Chile, di mana keberadaan Komisi Kebenaran tidak perlu menghalangi kebutuhan untuk melakukan investigasi dan bahkan jika terbukti, penghukuman atas para pelaku yang bertanggungjawab. Komisi mendapati bahwa pemberian amnesti yang dipergunakan untuk melindungi para pelaku kejahatan HAM berat pada saat bersamaan merupakan melanggar kewajiban HAM sebuah Negara. Berkenaan dengan kasus tersebut, pemerintah berpendapat bahwa amnesti haruslah ditempatkan di dalam konteks rekonsiliasi, yakni sebagai keharusan hukum yang dibutuhkan demi kebaikan bersama, karena “penyelidikan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu dapat PEC Translation Unit – 2006 7 menghidupkan kembali kebencian antar-pribadi atau pun kelompok”; dan oleh karenanya mengganggu penguatan institusi-institusi demokratis [yang tengah berkembang]. Pemerintah juga mengajukan argumentasi bahwa amnesti tersebut telah diberikan oleh rezim militer terdahulu, dan juga bahwa mereka [pemerintahan yang berkuasa kini] tidak bertanggungjawab atas tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Pertama-tama Komisi berpandangan bahwa berkenaan dengan prinsip kesinambungan Negara (continuity of the State), tanggungjawab internasional tetaplah mengikuti Negara tersebut, terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pemerintahannya. Kedua, Komisi juga berpandangan bahwa terlepas dari Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi serta kerja-kerja yang telah dicapainya dalam mengumpulkan informasi tentang berbagai pelanggaran HAM di masa lalu; serta terlepas dari Undang-Undang Reparasi3—sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 25, dan sesuai dengan Pasal 1(1) dan Pasal 2 Konvensi HAM Amerika—selama hak untuk mendapatkan keadilan belum terpenuhi, semua kriteria ini tidaklah mencukupi untuk menjamin penghormatan terhadap korban pelanggaran HAM, yang berarti mencangkup juga pemenuhan keadilan di dalam kasus-kasus yang Undang-Undang Reparasi Chile menyediakan hal-hal berikut ini bagi para keluarga korban (a) uang pensiun seumur hidup dengan jumlah tidak kurang dari pendapatan rata-rata keluarga di Chile, (b) prosedur khusus untuk menyatakan sah atau tidaknya sebuah kematian, (c) perhatian khusus yang diberikan negara dalam hal kesehatan, pendidikan dan perumahan, (d) pengampunan terhadap semua bentuk hutang pajak, pendidikan, dan semua hutang yang dipikul korban terhadap negara, dan (e) pembebasan dari wajib militer bagi anak-anak korban. 3 PEC Translation Unit – 2006 8 spesifik, menghukum para pelaku, serta menyediakan reparasi yang patut pula untuk korban dan keluarganya. Carmelo Soria Espinoza vs. Chile, Kasus 11.725, Laporan Nº 133/99, OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. at 494 (1999).4 Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) juga telah menyatakan hal serupa, bahwa mekanisme pemulihan korban yang berbeda-beda sebenarnya independen—jadi yang satu tidak bisa digunakan untuk menggantikan yang lainnya—dan juga bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menghukum para pelaku sekaligus memberikan kompensasi bagi korban. Di dalam kasus X dan Y vs. the Netherlands, tanggal 26 Maret 1985, Series A, No. 91, Hukum Belanda menyatakan bahwa pengaduan kasus pidana haruslah diajukan oleh korban di dalam batas waktu yang telah ditentukan; Nona Y telah mengalamai kekerasan seksual, namun karena ia memiliki gangguan mental, maka adalah sang ayah yang akhirnya mengajukan pengaduan, yang kemudian ternyata dikesampingkan oleh jaksa penuntut. Pemerintah berpendapat bahwa kemampuan untuk mengajukan gugatan hukum secara perdata terhadap para pelaku kejahatan sudahlah merupakan bentuk pemulihan yang cukup, akan tetapi pengadilan tidak Lihat juga kasus-kasus serupa, yang melibatkan Argentina, Uruguay, dan El Salvador. Semua negara ini berada dalam situasi transisi dari pemerintahan militer menuju pemerintahan sipil. Lihat misalnya kasus 28/92 (Argentina) and 29/92 (Uruguay), Laporan Tahunan Komisi HAM InterAmerika (Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights), OEA/Ser.L./V/II.98 (1997). Oleh karena itu kewajiban untuk menegakkan keadilan tidak memperbolehkan pemberian amnesti yang melanggar hak-hak korban bagi remedy dan didengarkan kesaksiannya secara patut, juga telah dikonfirmasikan oleh Pengadilan HAM Inter-Amerika di dalam Kasus Barrios Altos, Putusan bulan Maret 14, 2001, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 75 (2001). 4 PEC Translation Unit – 2006 9 sependapat. Perlindungan yang diberikan oleh hukum perdata (civil law) tidaklah memadai di dalam konteks pelanggaran yang tengah kita bahas di sini, terutama karena pelanggaran tersebut telah menginjak nilai-nilai fundamental: hanya ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dapat menegakkan efek jera yang efektif, dan memang ketentuan-ketentuan ini pula yang secara normal mengatur perkara semacam ini. Dengan demikian, tidak terdapat mekanisme yang cukup efektif untuk mendapatkan pemulihan. Untuk pelanggaran pidana yang serius, setidaktidaknya kemungkinan bagi penuntutan dapat disyarakatkan di bawah Konvensi Eropa (European Convention), namun pemulihan yang bersifat perdata tidaklah akan memadai. Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari perspektif seragam atas treaty bodies [badan atau lembaga PBB yang dibentuk berdasarkan Kovenan atau Konvensi PBB) yang telah dijabarkan di atas tentang tema kita: pertama, hak atas kebenaran, keadilan, serta hak atas reparasi adalah bersifat independen (sungguh pun merupakan kewajiban yang saling-terkait); dan kedua, bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi ketiga-ketiganya bagi para korban. Ketiga hal tersebut tidaklah boleh diikat secara bersama dan dibuat bergantung satu sama lain, karena ini akan bertentangan dengan konsep kewajiban yang independen. Dikarenakan Pasal 27 Undang-Undang KKR menetapan aturan seperti ini, maka Undang-Undang KKR telah melanggar kewajiban-kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional. Sebagai tambahan, dengan PEC Translation Unit – 2006 10 mengikatkan reparasi korban pada identifikasi dan tindakan dari pihak pelaku, Undang-Undang KKR telah menciptakan pembedaan yang bersifat sewenang-wenang di antara para korban yang mengalami situasi serupa, serta melanggar pula hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang setara sebagaimana telah dijamin di dalam berbagai instrumen HAM.5 Kedua, pemberian salah satu hak [korban], namun melupakan hak lainnya tidaklah memadai. Dengan demikian, dengan ditutupnya hak korban atas keadilan melalui menutup akses korban pada Pengadilan HAM—khususnya ketika korban tidak bisa menerima permintaan maaf maupun pemberian amnesti para untuk pelaku—maka Pasal 44 telah melanggar kewajiban-kewajiban di muka. Dan akhirnya, dengan dibatasinya hak korban atas keadilan di dalam kasus kejahatan yang paling serius, seperti telah didiskusikan di atas, maka Pasal 1 (9) UndangUndang KKR juga bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 7 Deklarasi Universal HAM; Pasal 26 ICCPR; Pasal 14 Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental manusia; Pasal 24 Konvensi Amerika tentang HAM; Pasal 3 Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi dan Hak-Hak Masyarakat; Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial. 5 PEC Translation Unit – 2006 11 2. Siapakah Korban? Definisi paling memadai tentang korban di dalam hukum internasional terdapat pada Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, untuk selanjutnya akan dirujuk sebagai ‘Prinsip-Prinsip Dasar’ saja), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34 pada tanggal 29 November 1985. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa: 1.”Korban” adalah orang yang—secara individual ataupun kolektif— telah menderita kerugian, baik dalam bentuk cidera fisik ataupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis, atau pengrusakan fundamental hak-hak mereka, lewat berbagai tindakan (acts) atau pembiaran (omissions) yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku dan diakui oleh Negara-Negara Pihak, termasuk berbagai Undang-Undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana. 2. Berdasarkan Deklarasi ini, seseorang dapat dianggap korban, tidak tergantung pada faktor apakah pelakunya telah dikenali, ditangkap, dituntut atau pun dinyatakan bersalah, dan terlepas dari hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah “korban”—sejauh patut—juga mencangkup keluarga dekat ataupun tanggungan langsung dari sang korban, dan orang-orang yang menanggung kerugian-kerugiaan karena memutuskan untuk mendampingi korban yang telah terkena dampaknya, atau mencegah jatuhnya korban. 3.Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk semua orang, tanpa pembedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, serta persepsi politik atau paham lainnya; terlepas dari kepercayaan maupun praktik-praktik kultural, hak milik, status kelahiran ataupun keluarga, akar-akar sosial ataupun etnis, serta menderita cacat atau tidak. Dengan demikian Prinsip-Prinsip Dasar tersebut telah memperjelas bahwa status sebagai korban tidaklah tergantung pada diidentifikasi atau PEC Translation Unit – 2006 12 dikenalinya sang pelaku, atau pun pada proses pemberian amnesti. Korban tidak alasannya, boleh sehingga mengalami terlepas perlakuan dari persoalan diskriminatif apakah apa para pun pelaku kejahatan yang menimpa “mereka” telah ditemukan atau belum. Penetapan mengenai siapa yang merupakan korban adalah sepenuhnya merupakan permasalahan hukum internasional. Definisi yang sama tentang korban juga digunakan untuk merumuskan ketetapan internasional kemudian, seperti Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Para Korban Kejahatan HAM Berat serta Pelanggaran-Pelanggaran Serius di dalam hukum internasional (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) (selanjutnya disebut Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman), yang diakui oleh Komisi HAM PBB pada tahun 2005. Penting untuk dicatat bahwa di dalam pembukaan Prinsip-Prinsip Dasar (Basic Principles), banyak negara telah menyetujui bahwa mereka “tidak melihatnya sebagai kewajiban baru tetapi mengidentifikasi… [hal ini] sebagai kewajiban hukum yang telah berlaku sebelumnya”. Dengan demikian mereka sesungguhnya mengemukakan kembali mengenai kewajiban internasional yang secara umum telah diterima oleh banyak Negara. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar tersebut Negara pihak tidak hanya memenuhi hak korban atas pemulihan dan reparasi tetapi mereka juga harus: PEC Translation Unit – 2006 13 Memastikan bahwa hukum nasional mereka menyediakan minimal perlindungan yang sama bagi kroban dengan yang telah ditentukan oleh hukum internasional (Prinsip-Prinsip Dasar 2(d)); dan Memberikan korban kejahatan terhadap HAM atau pun hukum humaniter akses terhadap keadilan yang efektif dan setara, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dengan tidak perlu melihat siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang telah terjadi (PrinsipPrinsip Dasar 3(c)) dan Menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban, termasuk hak atas reparasi, seperti telah dijelaskan sebelumnya (Prinsip-Prinsip Dasar 3(d)). Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tersebut menekankan bahwa “Seseorang dapat dianggap sebagai korban tidak tergantung dari apakah pelaku dari kejahatan yang menimpa korban tersebut telah diidentifikasi, ditangkap, dihukum, atau pun dituntut, dan tidak tergantung pada relasi keluarga antara pelaku dan korban.” (Prinsip-Prinsip Dasar 9). Hak untuk mendapatkan remedy (pemulihan) terus bertumbuh mencangkup orang-orang yang ikut terkena dampak pelanggaran HAM secara tidak langsung. Di dalam Pasal 8 Deklarasi Universal HAM dinyatakan bahwa setiap orang yang terkena pelanggaran hak-hak fundamental, baik secara langsung atau pun tidak, berhak memperoleh hak atas pemulihan. Pasal 2(3) dari Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik (yang telah diratifikasi Indonesia) mendefinisikan korban (yang berhak dipenuhi hak-hak fundamentalnya) sebagai “setiap orang yang hak-hak dan kebebasannya… dilanggar”, dan menekankan bahwa Negara harus memberikan pemulihan yang efektif terhadap “setiap orang (korban) PEC Translation Unit – 2006 yang mengklaim pemulihan semacam itu. Untuk 14 mengganti ketetapan yang berkaitan dengan pemulihan di Pasal 2(3), Konvensi menetapkan hak atas kompensasi bagi pelanggaran HAM dalam bentuk penahanan paksa atau pun pelanggaran atas kebebasan. Pasal 9(5) menyatakan bahwa, “setiap orang yang telah menjadi korban dari penahanan paksa atau pun penghilangan paksa haruslah mendapatkan hak atas kompensasi”. Proses perumusan ketetapan ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang sebelum merupakan pengecualian akhirnya dibatalkan. Sebagai gantinya, mayoritas perumus ketetapan tersebut memutuskan bahwa kompensasi haruslah diberikan oleh Negara dan tidak hanya oleh pelaku atau pun pejabat yang terkait, terutama karena pejabat maupun pelaku yang terkait akan memberikan kompensasi hanya kepada kasus-kasus, di mana pelakunya telah teridentifikasi.6 Pasal 14 Konvensi Anti Penyiksaan (yang telah diratifikasi oleh Indonesia) menekankan bahwa “korban dari tindak kekerasan dan penyiksaan” berhak mendapatkan kompensasi yang adil dan mencukupi. Pasal 13 Konvensi Eropa tentang Perlidungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia, serta Pasal 25 Konvensi Amerika tentang HAM juga menekankan bahwa “setiap orang yang mengklaim pemulihan semacam itu” haruslah mendapatkan kompensasi yang efektif. Di dalam sistem hukum Eropa, “pihak yang mengalami kerugian langsung adalah sinonim dari ‘korban’…, dan oleh karena itu mencangkup ‘orang-orang Untuk lebih rinci lihat Naomi Roht-Arriaza, Impunity and Human Rights in International Law and Practice (Oxford University Press, 1995), Bab 3. 6 PEC Translation Unit – 2006 15 yang terkena dampak langsung dari segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketetapan Konvensi’.”7 Definisi korban tidaklah perlu tergantung pada ketetapan hukum nasional. Pengadilan HAM Inter-Amerika di dalam kasus of Bámaca vs. Guatemala, tanggal 22 Februari, 2002, Ser. C No. 91, menyatakan bahwa: Reparasi atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran atas hukum internasional sedapat mungkin mewajibkan pemberian restitusi secara penuh (restitutio in integrum), dan hal ini juga termasuk menegakkan kembali situasi semula [sebelum terjadinya pelanggaran]. Jika hal ini tidak dimungkinkan terutama di dalam kasus-kasus tertentu, maka pengadilan internasional haruslah menentukan kriteria tertentu—di samping untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang telah dilanggar—juga harus memperbaiki akibat-akibat yang muncul karena pelanggaran, seperti menetapkan kompensasi dan ganti kerugian atas kerusakan yang telah terjadi. Kewajiban untuk memenuhi hak reparasi dan semua aspeknya diatur di dalam hukum internasional (jangkauan, hakikat, etika, maupun pihak yang merupakan tanggungannya) dan tidak dapat diubah oleh Negara, atau ditolak dengan memilih untuk menggunakan ketentuan hukum yang bersifat domestik [penekanan/cetak miring saya tambahkan, alinea 3]). Hal ini berjalan searah dengan Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties), yang menyatakan bahwa: “Negara pihak tidak boleh menggunakan hukumhukum yang bersifat domestik sebagai pembenaran atas kegagalan mereka untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan.” Dengan demikian, di dalam General Comment 31 dari Komite HAM, yang menafsirkan kewajiban Negara di bawah otoritas Kovenan Internasional Peter van Dijk, G.J.H. van Hoof, bekerjasama dengan W. Herring et.al., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, (Third Edition, Lower Law International, Hague/London/Boston, 1998), hlm. 248. 7 PEC Translation Unit – 2006 16 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (tanggal 29 Maret 2004), Komite menulis: 1. Walaupun Pasal 2, paragraf 2, memperbolehkan Negara-Negara Pihak untuk menerapkan Konvensi sesuai dengan proses konstitusional domestik (di level nasional), namun prinsip yang sama juga dapat digunakan untuk mencegah Negara-Negara Pihak menggunakan hukum domestik (nasional) demi membenarkan kegagalan mereka melaksanakan kewajiban, seperti yang telah tercantum di dalam perjanjian ini. Setiap individu berhak mengklaim status sebagai korban jika mereka telah memenuhi definisi yang telah dipaparkan. Ini merupakan formulasi umum untuk menentukan kredibilitas korban. Di dalam kasus Caracazo vs. Venezuela, Pengadilan HAM Inter-Amerika tertanggal 29 Agustus 2002 menyatakan bahwa: Setiap Negara Pihak yang terikat dengan Konvensi Amerika (American Convention) ini memiliki tugas untuk menginvestigasi tindak pelanggaran HAM dan kemudian menghukum para pelaku setelah pelanggaran tersebut telah dinyatakan sebagai faktual. Dan setiap orang yang menganggap dirinya sebagai korban dari pelanggaran semacam itu memiliki hak untuk mendapatkan akses pada sistem hukum yang adil dan memperoleh kompensasi dari Negara, demi kebaikannya dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan (alinea 115) (Cetak miring/penekanan dari saya).8 Anggota keluarga juga dapat didefinisikan sebagai korban, karena keterkaitannya dengan pihak yang mengalami pelanggaran HAM berat. Sementara Konvensi Amerika tentang HAM tentu saja tidaklah mengikat bagi Indonesia, namun patut dicatat mengenai ketentuan Konvensi Amerika yang diinterpretasikan oleh Pengadilan sebagaimana terlihat di dalam Pasal 1(1), yang mewajibkan para Negara Pihak untuk …”menghormati semua hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya, dan menjamin bahwa semua orang yang tunduk di bawah yurisdiksinya agar dapat melaksanakan hak dan kebebasan mereka secara bebas dan sepenuhnya”. Ketentuan ini nyaris identik dengan Pasal 2(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang berketetapan bahwa para Negara Pihak haruslah “menghormati dan menjamin hak yang diakui di dalam Kovenan ini atas setiap orang yang berada di dalam cakupan wilayah dan tunduk di bawah kewenangannya”. 8 PEC Translation Unit – 2006 17 Misalnya di dalam kasus Pengadilan HAM Eropa, Kurt vs. Turkey, (15/1997/799/1002), di mana ibu dari orang yang hilang dianggap sebagai korban dan diberikan status sebagai pihak yang mengajukan tuntutan. Pengadilan beranggapan bahwa pelanggaran atas hak kebebasan dan keamanan yang dialami oleh anak dari ibu tersebut, yang diatur di Pasal 5 dari Konvensi (alinea 129) adalah sah, sehingga kompensasi diberikan kepada ibu tersebut atas nama anak yang telah dilanggar hak-haknya (alinea 174). Dan kemudian pengadilan tidak menanggapi pengaduan atas pelanggaran HAM dalam bentuk penyiksaan atau pun perlakuan yang merendahkan martabat manusia lainnya dan memberikan penghukuman terhadap pelaku atau pun memberikan pemulihan yang memberikannya efektif sejumlah terhadap uang ibu dalam korban tersebut, statusnya sebagai tetapi korban berdasarkan pada penderitaan serta kecemasan mentalnya, karena tidak mengetahui nasib dari anaknya (alinea 175). Di dalam yurisprudensi Pengadilan HAM Inter-Amerika, pelanggaran terhadap hak-hak tertentu membuat individu yang terkait dengan korban justru mendapat status sebagai korban tanpa perlu lagi memeriksa kondisi-kondisi lainnya. Pelanggaran terhadap hak hidup dalam bentuk eksekusi mati tanpa dasar hukum (extra-judicial executions) serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak hidup lainnya dalam bentuk penghilangan paksa atau pun praktik penyiksaan maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya tercakup ke dalam kategori ini. Sungguhpun lazimnya di dalam kasus-kasus PEC Translation Unit – 2006 18 tertentu ada faktor-faktor lain yang meningkatkan kadar pelanggaran— baik karena kematian secara keji dan penyiksaan dalam tingkat yang sangat berat—dan semua hal yang menghasilkan penderitaan langsung, kesemuanya ini membuat status dari orang-orang terdekat dengan pihak korban secara langsung menjadi korban pula tanpa tanpa perlu pembuktian lebih jauh.9 Dengan demikian di dalam hukum internasional definisi korban dirumuskan secara luas. Kualifikasi sebagai korban seketika terpenuhi pada saat pelanggaran/kejahatan tersebut dilakukan dan terlepas dari hukum nasional, atau pun proses penentuan hak mereka atas reparasi. Dengan kata lain, seseorang mendapat status sebagai korban, ketika status tersebut telah ditetapkan, dan Negara tidak dapat mengubah status tersebut tanpa persetujuan langsung dari korban. Dengan membuat status korban bergantung dari pengidentifikasian pelaku serta amnesti terhadap pelaku tersebut, Pasal 27 Undang-Undang KKR telah melanggar hak korban atas reparasi dan pemulihan. 3. Praktik di Negara-Negara lain: Bagaimana Negara-Negara lain memenuhi kewajiban menegakkan kebenaran, keadilan dan reparasi Undang-Undang KKR Indonesia memiliki mekanisme yang berlawanan dengan praktik-praktik yang tengah diberlakukan oleh Kasus Paniagua Morales dkk, putusan mengenai reparasi tertanggal 25 Mei 2001, alinea 142; Kasus Trujillo Oroza, putusan mengenai reparasi tertanggal 27 Februari 2002, alinea 85. 9 PEC Translation Unit – 2006 19 Negara-Negara lain di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia, belasan Negara telah membentuk Komisi Kebenaran tidak hanya untuk mengatasi masa lalu mereka (come to terms with their own past), tetapi juga untuk memenuhi kewajiban internasional atas investigasi dan pemenuhan hak korban atas kebenaran. Mereka telah menegakkan mekanisme reparasi tersendiri untuk memenuhi kewajiban mereka memperbaiki berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Praktik-praktik terbaik dari Negara-Negara ini menunjukkan melaksanakan program yang bahwa menanggapi berbagai dan Negara dapat dapat memenuhi kebutuhan nasional serta sambil memenuhi dan tidak melanggar kewajiban-kewajiban mereka di hadapan hukum internasional. Praktikpraktik ini juga telah membantu untuk menafsirkan—melalui tindakan Negara-Negara selanjutya—arti internasional, seperti dalam dari hal ketetapan kewajiban dan untuk perjanjian memastikan pemenuhan berbagai hak maupun penyediaan hak atas pemulihan.10 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang KKR memiliki perbedaan di dalam struktur dan mandat kerja mereka dengan praktik di level dunia. Perbedaan tersebut setidaknya menyangkut empat hal: 1. Tidak ada ketentuan mengenai proses penelurusan kembali segala sebab, konteks, atau pun pola dari kekerasan yang telah terjadi, dan hanya dibatasi untuk “peristiwa” khusus, yang juga tidak membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan satu Lihat Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, bulan Mei 23, 1969, U.N. Doc. A/CONF.39/27, Pasal 31(3)(b). 10 PEC Translation Unit – 2006 20 peristiwa dengan perisitwa lainnya. Semua hal ini biasanya ditentukan dari kompilasi laporan yang telah dimiliki sebelumnya. 2. Tidak ada kewajiban bagi Komisi Kebenaran untuk membuat rekomendasi yang bertujuan mencegah berulangnya kembali pelanggaran yang telah terjadi di masa depan. 3. Kriteria reparasi digantungkan pada faktor eksternal yang terlepas dari korban. 4. Amnesti—sungguh pun memiliki sifat bersyarat—ternyata diberikan juga bagi kejahatan-kejahatan tidak boleh mendapatkan amnesti (non-amnestiable crimes). Saya akan memusatkan diri pada dua perbedaan terakhir, walaupun saya juga mengetahui bahwa perbedaan pertama juga dapat menjadi pelanggaran kebenaran, terhadap sebagaimana yang hak korban telah diatur untuk di mendapatkan dalam instrumen internasional. Mengaitkan amnesti dengan reparasi: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mengaitkan pengungkapan kebenaran dengan amnesti. Akan tetapi, Komisi Kebenaran [Afrika Selatan] memiliki komite yang terpisah yang bertugas merumuskan rekomendasi atas reparasi kepada korban; dan pemerintah akan memberikan reparasi—baik secara kolektif maupun individual— kepada orang-orang yang diberikan status sebagai korban berbasiskan pernyataan Komisi Kebenaran atau pun sebaliknya. Berbagai Komisi Kebenaran lainnya telah merekomendasikan semacam program reparasi. Akan tetapi proses ini dirumuskan melalui mekanisme administratif yang berbeda. Dalam beberapa kasus proses pemberian pernyataan atau pun PEC Translation Unit – 2006 21 testimoni di hadapan Komisi kebenaran sudahlah mencukupi bagi seseorang untuk mendapatkan reparasi. Sementara untuk kasus-kasus lainnya program reparasi menggunakan mekanisme seleksi tertentu, seperti di dalam kasus penahanan tanpa proses hukum selama waktuwaktu tertentu, atau pun kehilangan anggota keluarga selama periode tertentu, haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu untuk mendapatkan reparasi. Komisi Kebenaran sendiri dapat juga melakukan investigasi dan jika bukti-bukti dari korban telah memadai, mereka dapat memberikan reparasi. Akan tetapi, tidak pernah ada kasus, di mana korban dipaksa untuk memilih antara memberikan amnesti kepada para pelaku untuk mendapatkan reparasi. Ini adalah pilihan yang kejam, yang melanggar hak korban untuk diperlakukan secara hormat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Negara memiliki peran yang sangat besar dalam proses merumuskan dan menerapkan program reparasi. Akan tetapi peran ini tidaklah boleh bertentangan dengan kewajiban internasional. Hukum internasional menetapkan batas terjauh tentang apa yang dapat dilakukan oleh Negara, dan di sini batas-batas tersebut telah dilampaui. Mekanisme reparasi haruslah komprehensif, adil, koheren dengan kewajiban lainnya, dan jumlahnya harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang terjadi dan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi haruslah dilakukan dengan kehendak baik. Pasal 27 Undang- PEC Translation Unit – 2006 22 Undang KKR, secara khusus, tidaklah konsisten dengan norma-norma ini, maupun dengan praktik internasional. Batas-batas amnesti: Hukum internasional memperbolehkan diterapkannya amnesti dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali pihak-pihak yang berkonflik, dan untuk banyak kejahatan lainnya di dalam hukum nasional. Betapapun juga amnesti tidaklah diperbolehkan atas sejumlah kejahatan-kejahatan berat (grave crimes) tertentu. Yang paling pokok di antara kejahatan-kejahatan berat tersebut antara lain adalah: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang justru diberikan amnesti di dalam Undang-Undang KKR Indonesia. Pertimbangan di muka adalah posisi yang telah disepakati secara bulat oleh instrumen-instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi mengenai Pencegahan Genosida tahun 1948 (Pasal 5 dan 6), Konvensi Jenewa tahun 1949 (Pasal 49, 50,129 dan 146, Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 5 dan 7), Konvensi Internasional tentang Perlindungan dari Penghilangan Paksa yang ditetapkan baru-baru (Pasal 11), Rangkaian Prinsip Terbaru dalam Promosi dan Perlindungan HAM melalui Aksi Memerangi Impunitas (Updated Set of Principles on the Promotion and Protection of Human Rights Through Action to Combat Impunity) (Rangkaian Prinsip 19, 24); Prinsip-Prnsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Para Korban Kejahatan HAM Berat dan Kejahatan Serius Hukum Humaniter Internasional (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for PEC Translation Unit – 2006 23 Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) (Pasal III (4)). Hal ini juga merupakan posisi yang diadopsi oleh berbagai badan pakar internasional, seperti Komite HAM PBB di dalam berbagai kesimpulan mereka, serta kasus-kasus individual di dalam General Comment 20, ketika membahas tentang penyiksaan mereka mendapati bahwa “amnesti tidaklah sejalan dengan kewajiban Negara untuk menginvestigasi setiap tindak pelanggaran HAM, untuk menjamin tidak terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut di dalam yurisdiksi mereka, serta untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak lagi terjadi di masa depan”. ICCPR General Comment 20 (sesi 44, 1992), Pasal 7: menggantikan General Comment 7 menyangkut Larangan Penyiksaan, Perlakuan dan Penghukuman yang Tidak Manusiawi, A/47/40 (1992) 193 alinea 15. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa “PBB mendukung terciptanya kesepakatan damai, dan tidak pernah akan menyetujui amnesti bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida atau pun bentuk-bentuk kejahatan HAM berat lainnya.” PBB juga menyimpulkan bahwa dengan mendorong terciptanya kesepakatan damai, dan merumuskan resolusi dewan keamanan yang “menolak semua bentuk amnesti terhadap kejahatan perang, pembunuhan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk yang berkaitan dengan kejahatan berbau etnis, gender, dan seksual, yang diatur didalam hukum PEC Translation Unit – 2006 24 internasional, sekaligus juga memastikan bahwa tidak ada amnesti yang diberikan sebelum PBB menciptakan pengadilan pendamping”. Dewan Keamanan, Laporan mengenai Supremasi Hukum dan Keadilan Transisional di Dalam Masyarakat Konflik dan Pasca-Konfilik (Report On The Rule Of Law And Transitional Justice In Conflict And Post-Conflict Societies), Sekretaris Jenderal, UN. Doc. S/2004/616, (tanggal 3 Agustus 2004) alinea 10. Pada tahun 2001 Pengadilan HAM Inter-Amerika di dalam kasus Barrios Altos, menyatakan bahwa: “Pengadilan menyatakan bahwa semua ketetapan amnesti, ketetapan tentang perumusan kriteria yang digunakan untuk menghapus mekanisme pertanggungjawaban tidaklah dapat diterima, karena ketetapan tersebut mencegah penyelidikan dan penghukuman terhadap para pelaku yang bertanggungjawab terhadap kejahatan HAM berat, seperti penyiksaan, penculikan paksa, pembunuhan, kesemuanya itu dilarang, karena melanggar hak-hak dasar yang diatur di dalam hukum HAM internasional.” Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Peru), March 14, 2001. Peru kemudian mengganti kebijakan amnestinya setelah menanggapi keputusan ini. Pada tahun 1998 Trial Chamber of the International Criminal Tribunal atas bekas Yugoslavia menyatakan bahwa suatu amnesti bersifat domestik (nasional) yang berkaitan dengan kejahatan seperti penyiksaan dan semua bentuk kejahatan lainnya yang memiliki status jus cogens merupakan pelanggaran atas kewajiban erga omnes; dan tidak sesuai dengan pengakuan atas hukum internasional. Prosecutor vs. Furundzija, putusan tertanggal 10 Desember 1998, alinea 155. PEC Translation Unit – 2006 25 Pengadilan nasional maupun pengadilan campuran (hybrid courts) juga telah mendapati bahwa amnesti untuk kejahatan-kejahatan internasional tidaklah sejalan dengan kewajiban Negara, sehingga tidak perlu untuk dipatuhi. Misalnya, Ould Dah case, French Court of Cassation Oct. 23, 2002 (tidak perlu mematuhi hukum amnesti); Kasus-kasus Argentina maupun Chile di hadapan Audiencia Nacional Spanyol (Pleno), Nov. 5 1998 (sama); Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad. Kasus Mahkamah Agung Argentina, kasus No. 17.768 (14 Juni 2005) S.1767.XXXVIII (menyetujui pencabutan hukum amnesti atas dasar hukum internasional); Juan Contreras Sepúlveda y otros (crimen) casacion fondo y forma, Chilean Supreme Court, 517/2004. Resolución 22267, Januari 2005 (amnesti tidaklah berlaku di dalam kasus penghilangan paksa dan bertentangan dengan Konvensi Jenewa); Pengadilan Khusus Sierra Leone, Indictment and Decision on Review of Indictment and Application for Consequential Orders (24 Mei 1999); Prosecutor vs. Charles Ghankay Taylor, Case No.SCSL-03-01, Indictment (3 Maret 2003)(amnesti yang bersifat domestik tidak berlaku untuk kejahatan internasional). Di masa lalu berbagai Komisi Kebenaran memperbolehkan amnesti hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan pengungkapan penghukuman PEC Translation Unit – 2006 sendiri kebenaran terhadap merumuskan secara pihak-pihak kebijakan utuh, yang yang tidak amnesti sejalan mau untuk dengan membuat 26 permohonan amnesti atau yang tidak mengakui keterlibatan penuh mereka dan juga terkait dengan reparasi yang diberikan kepada korban. Secara kontras, Undang-Undang Indonesia memungkinkan penolakan terhadap amnesti, sementara korban tetap tidak bisa melanjutkan kasusnya ke pengadilan HAM, karena kasusnya telah disidangkan di Komisi Kebenaran. Amnesti—dengan persyaratan tertentu—ditambah dengan penghukuman yang dirumuskan oleh Komisi Kebenaran Afrika Selatan telah gagal menjerat perwira tinggi pemerintahan dan tentara untuk mengakui keterlibatan mereka di dalam pelanggaran HAM. Pada 1996, ketika semua proses telah selesai dilakukan, pelarangan terhadap semua bentuk amnesti kembali diterapkan dan diperkuat. Kebijakan amnesti lainnya juga diterapkan didalam proses perdamaian di Sierra Leone, yang pemerintahannya membentuk Komisi Kebenaran pula. Pada masa itu, perwakilan dari PBB menentang penerapan ketetapan amnesti tersebut, karena ketetapan tersebut memberikan amnesti terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang tidak boleh mendapatkan amnesti menurut hukum internasional. Beberapa bulan kemudian, pemerintahan Sierra Leone, bersama dengan delegasi PBB, menciptakan Pengadilan Khusus Sierra Leone untuk mengadili para pelaku yang bertanggungjawab terhadap kejahatan HAM internasional. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa hukum amnesti domestik hanya berlaku di pengadilan domestik (nasional) dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat nasional. Di Timor Timur, Komisi untuk Kebenaran, PEC Translation Unit – 2006 27 Penerimaan dan Rekonsiliasi (Commission for Truth, Reception and Reconciliation—CAVR) memiliki prosedur yang memberikan amenesti, tetapi hanya pada beberapa kejahatan tertentu. Kejahatan HAM berat dan terutama kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihadapi melalui proses penghukuman. berhadapan Beberapa dengan Negara kejahatan lainnya masa telah lalu, melakukan tetapi mereka proses tidak menggunakan mekanisme Komisi Kebenaran. Walaupun begitu, NegaraNegara tersebut juga tidak memberikan amnesti terhadap para pelaku kejahatan HAM berat, yang diatur di bawah hukum internasional. Di Rwanda, mereka menciptakan pengadilan lokal tradisional, yang menetapkan hukuman pelayanan publik alih-alih menghukum penjara para pelaku yang telah mengaku. Akan tetapi, mekanisme ini berbeda dari amnesti, dan memiliki pola penghukuman yang berbeda. Dalam banyak kasus, proses lokal ini tidak berlaku bagi pemimpin ataupun perancang dari pembunuhan massal, ataupun para pemerkosa. Di Colombia, seperti yang telah disadari oleh pengadilan, Undang-Undang Perdamaian dan Keadilan memperbolehkan untuk mengurangi penghukuman yang berjalan searah dengan reparasi korban, penuturan kebenaran, serta lima tahun penjara, tetapi bukanlah amnesti. UndangUndang Rekonsiliasi Nasional Guatemala (Guatemalan Law of National Reconciliation) melegalkan amnesti, tetapi tidaklah terhadap pelaku kejahatan genosida, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang diatur di dalam hukum internasional. Komisi Kebenaran PEC Translation Unit – 2006 28 di Maroko, Ghana, Peru, Panama, dan Liberia, kesemuanya dibentuk pasca Komisi Kebenaran Afrika Selatan, tidak memiliki ketentuan yang memperbolehkan amnesti. Liberia menggunakan konsep “imunitas” yang otoritasnya diberikan kepada Komisi Kebenaran, tetapi itu pun bukanlah amnesti. Kesemua Negara ini telah menyadari pentingnya proses rekonsiliasi setelah konflik mereda. Negara-Negara tersebut juga telah menemukan mekanisme yang sesuai dengan kewajiban yang dirumuskan didalam hukum internasional menghormati hak untuk korban mendorong atas proses kebenaran dan rekonsiliasi, keadilan. yang Hukum internasional tidaklah memberikan resep instan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Negara setelah konflik mereda, tetapi hukum internasional memberikan batas-batas tertentu, semacam pagar, di mana sebuah Negara dapat berjalan konsisten dengan kewajiban hukum yang dirumuskan secara internasional. Undang-Undang KKR di Indonesia bertentangan dengan ketetapan internasional tersebut. Undang-Undang KKR telah membuat hukum Indonesia melanggar berbagai perjanjian internasional secara khususnya dan melanggar hukum internasional secara umum. PEC Translation Unit – 2006